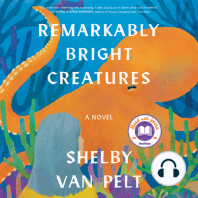Foto Jurnalistik
Diunggah oleh
Wahmuji IjumhawHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Foto Jurnalistik
Diunggah oleh
Wahmuji IjumhawHak Cipta:
Format Tersedia
Teori Foto Jurnalistik Foto jurnalistik adalah sebuah pesan yang dibangun oleh tiga unsur, yakni sumber
pemancar, saluran transmisi dan pihak penerima. Sumber pemancar adalah seluruh insan pers di surat kabar yang bertugas untuk mengambil foto, memilih foto, menyusun, memberi caption, membuat judul. Saluran transmisi adalah surat kabar itu sendiri atau lebih tepatnya kompleks pesan dimana foto menjadi pusat dan dikelilingi teks, judul, caption, tata-letak, maupun bahkan terlingkupi dalam nama surat kabar itu sendiri. Pihak penerima adalah publik yang membaca surat kabar tersebut. Pemancar dan penerima pesan berada di ranah sosiologi. Kajiannya adalah tentang kelompok manusia atau pendefinisian motif dan sikap, atau usaha untuk menghubungkan kelompok-kelompok itu dengan masyarakat di mana mereka menjadi bagiannya. Sedangkan untuk pesan itu sendiri, metode kajiannya jelas berbeda. Tak peduli asal dan tujuan pesan, foto bukan hanya sebuah produk atau saluran tapi juga objek yang diberkati dengan sebuah otonomi struktural. Analisis otonomi struktural foto tidak dimaksudkan untuk memisahkan objek dari penggunaannya, akan tetapi diperlukan sebagai metode khusus sebelum analisis sosiologi dilaksanakan. Struktur foto bukanlah struktur yang terisolasi. Setidaknya,struktur itu berkomunikasi dengan satu struktur lain, yakni teks (judul, caption, atau artikel) yang menemani kehadiran foto. Meski demikian, karena unit-unit penyusunnya berbeda, mereka sebenarnya tetap terpisah. Dalam foto, substansi pesan dibangun dengan garis, tekstur, warna. Sedangkan teks disusun dengan kata-kata. Karena berbeda unsur penyusunnya, analisisnya pun pertama-tama harus terpisah juga. Untuk itu kita perlu memulainya dengan mencari tahu pesan dan kode dari foto. Pesan fotografis pada dasarnya adalah kenyataan harafiah. Tentu saja ada reduksi antara objek jepretan dan hasil foto dalam hal proporsi, perspektif, dan warna. Tapi reduksi itu bukanlah reduksi transformasi. Artinya, untuk mengubah dari realitas menjadi foto tidaklah perlu untuk memisah-misahkan realitas menjadi unitunit dan mengangkat unit-unit itu sebagai tanda. Tentu saja citra bukanlah realitas, tetapi ia merupakan analogon yang sempurna. Citra fotografis adalah pesan tanpa kode; ia adalah pesan yang terus-menerus. Kesempurnaan analogis itulah kekuatan foto. Dari sini kita bisa menarik akar dari seni-seni imitatif laingambar, lukisan, film, dan teater. Bidang seni itu terbangun dari dua pesan: pesan denotatif, yakni analogon itu sendiri; sedangkan pesan konotatifadalah cara masyarakat mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan mengenai seni itu. Akan tetapi foto berbeda. Pesan tingkat pertama dari foto memenuhi substansinya sehingga tidak meninggalkan tempat untuk berkembangnya pesan tingkat dua. Oleh karenanya, deskripsi foto secara harafiah tidak mungkin dilakukan. Untuk mendeskripsikan foto, seseorang harus langsung mengambil konotasinya, mengubah strukturnya, menandakan sesuatu yang berbeda dari apa yang ditunjukkan. Kode konotatif itulah yang harus dibangun. Untuk menguraikannya, diperlukan prosedur-prosedur konotasi. 1
Saya akan menjelaskan prosedur-prosedur konotasi dengan memakai sebuah foto jurnalistik yang dimuat di Kompas tanggal 2 Desember 2011 berjudul Rob di Kamal Muara. Sebelumnya, perlu dinyatakan bahwa tidak semua prosedur konotasi ada dalam satu foto. Setiap foto mungkin bisa dibaca dengan satu atau lebih prosedur konotasi. Prosedur konotasi yang pertama adalah efek tipuan (trick effect). Foto Rob di Kamal Muara tersusun atas gambar seorang anak sekolah yang berjalan di genangan rob, kanal beserta pembatas atau tanggulnya, rumah, jemuran, tempat pembuangan sampah, pipa air bersih, jembatan bambu, banner rokok Class Mild yang tergantung di teras sempit salah satu rumah), seorang pelajar lain di kejauhan yang sedang berjalan di atas pembatas kanal, dan laut. Dalam foto itu, fotografer menggunakan kredibilitas khusus dari foto, yakni bahwa foto adalah analogon dari kenyataan. Foto itu tampak alamiah, tapi sesungguhnya menyimpan efek tipuan. Kalau diperhatikan lebih rinci, kita akan segera menyadari bahwa foto yang ditonjolkan adalah seorang pelajar yang berjalan di genangan rob; ia tidak berjalan di pembatas kanal seperti foto seorang pelajar lainnya yang terambil secara samar; dan pelajar itu tampak bahagia. Mimik wajah pelajar itulah yang pertama-tama mengundang kecurigaan. Ia tersenyum dan tampak bahagia. Apakah itu mungkin? Ataukah ia sadar kamera tersenyum karena ada wartawan yang memotret? Apakah ia memang sudah dipersiapkan untuk difoto? Tampaknya memang demikian. Pelajar yang ditonjolkan itu juga berjalan di genangan rob, bukan di pembatas kanal. Tujuannya adalah untuk memberikan efek dramatis. Efek dramatis itulah penanda yang dibangun. Akan tetapi, ia hanya akan jadi tanda untuk masyarakat jika kita melihat nilai masyarakat pada zaman ini, terutama berkaitan dengan anak-anak, kemiskinan, dan bencana. Prosedur konotasi yang kedua adalah pose. Lagi-lagi, kita akan memperhatikan pelajar yang sedang berjalan di genangan rob. Ia kemungkinan besar sedang berangkat ke sekolah. Celananya dilipat dan ia membawa sandalnya dengan tangannya. Pelajar itu juga tersenyum. Keseluruhan sikap badan pelajar itu menandakan optimisme dan kegigihan; meskipun sedang dilanda bencana, anakanak tetap berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Itulah pesan yang terkandung dalam foto inibukan pose dalam arti sikap badan dan mimik pelajar itu, melainkan pelajar-yang-sedang-berangkat-ke sekolah. Di sini, pembaca menerima sebuah denotasi sederhana dari apa yang sebenarnya merupakan struktur ganda, yakni denotasi-konotasi. Prosedur konotasi selanjutnya adalah objek. Dalam foto, makna juga bisa diambil dari objek-objek yang difoto. Objek bisa ditata sedemikian rupa oleh fotografer; atau orang yang bertugas menata-letak memilih sebuah foto dengan objek-objek tertentu. Kepentingannya: objek merupakan pembawa asosiasi ide (misalnya, rak buku = intelektualitas). Seperti disebutkan di muka, objek-objek dari foto itu adalah pelajar yang berjalan di genangan rob, kanal dan tanggul pembatasnya, jemuran, rumah dengan teras yang dihiasi spanduk Class Mild, perumahan sebagai latar pertama, laut (yang permukaannya lebih tinggi dari darat) sebagai latar kedua, pipa air bersih, jembatan bambu, tempat duduk dari bambu. Pemandangan (scene) itu seolah-olah langsung dan spontan sehingga tidak ada 2
penandaan. Semua objek merupakan unit-unit yang kesatuannya membentuk konotasi. Kita sudah akrab dengan petanda-petanda dari objek-objek itu sehingga kita mendapatkan makna konotatif pemukiman kumuh, bahwa orang miskinlah yang pertama-tama dan paling banyak menderita karena bencana. Prosedur konotasi yang keempat adalah fotogenia. Berangkat dari teori fotogenia yang telah dikembangkan oleh Edgar Morin dalam Le Cinema ou Ihomme imaginaire, Barthes menulis bahwa in photogenia the connoted message is the image itself (which is to say in general sublimated) by techniques of lighting, exposure and printing. Artinya, dengan menggunakan sumber cahaya yang berbeda, bukaan (exposure) berbeda, atau teknologi cetak yang berbeda, orang bisa mengarahkan dan membangun konotasi dari sebuah citra. Atau setidaknya berupaya untuk melakukannya. Dalam fotogenia, inventarisasi bisa dilakukan sejauh tiap-tiap bagian memiliki petanda penghubung dengan leksikon kulturalnya. Sederhananya, efek-efek ciptaan itu harus dikenal atau terhubung dengan kebudayaan. Uji coba pemberian efek bisa juga dipakai untuk membedakan efek-efek estetis dan efek-efek penanda (yang menandakan). Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat satu contoh foto yang mengandalkan teknik fotogenia sebagai pembangun utama konotasinya.
Citra di atas adalah foto yang diambil dari sebuah makam Perang Dunia II di Normandy, Perancis. Citra itu telah diubah sedemikian rupa dari aslinya. Foto asli diambil pada siang hari dengan cahaya yang cerah. Rumput kelihatan hijau dan salib kelihatan putih. Dalam foto gubahannya, selain salib semuanya gelap. Salib pun berwarna abu-abu. Dengan teknik pengubahan yang ekstrim itu, kita mendapatkan 3
gambaran yang benar-benar berbeda soal makam Perang Dunia II. Perang Dunia II tampak sangat suram dan kesuramannya masih kita rasakan sampai sekarang; di zaman ini pun, masih banyak perang dan masih banyak orang yang mati di medan perang. Foto Rob di Kamal Muara tidak terlalu mengandalkan teknik fotogenia. Tapi kita masih bisa melacaknya. Diperhatikan lebih cermat, kita akan melihat pengaburan (blurring) yang dilakukan pada latar yang agak jauh, dan fokus diarahkan pada anak kecil yang berjalan di genangan rob dan latar terdekatnya. Dengan kata lain, fokus diberikan pada objek terdekat dari kamera, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kita samar-samar saja melihat anak kecil lain (dengan seragam sekolah yang mirip dengan anak di depan) yang berjalan di atas tanggul pembatas kanal, bukan di genangan rob. Penekanannya adalah pada derita anak sekolah karena rob. Di situlah makna konotatifnya. Prosedur konotasi terakhir adalah estetisisme dan sintaksis. Dapat dikatakan bahwa foto Rob di Kamal Muara tidaklah terbangun konotasinya dari kedua prosedur itu. Keindahan bukanlah yang utama dari foto itu. Foto itu juga bukanlah foto seri; foto itu berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan foto-foto lain perihal Rob di Kamal Muara. Seperti dijelaskan di awal, struktur foto tidak terisolasi melainkan berkomunikasi dengan teks lain (judul, caption, artikel yang menemani/ditemani foto). Dalam foto Rob di Kamal Muara, setidaknya kita menemukan bahwa teman foto itu adalah judul dan caption. Berikut caption foto itu: Seorang pelajar melintasi Rob atau limpasan air laut yang menggenangi jalan di depan rumah warga di wilayah perbatasan Dadap, Tangerang, Banten, dengan wilayah Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (1/12). Genangan air terjadi sejak seminggu lalu walaupun kini sudah mulai surut. Ada tiga catatan yang diberikan oleh Roland Barthes perihal hubungan pertemanan teks dan foto. Pertama, teks merupakan pesan parasitis yang dirancang untuk mengkonotasikan citra, untuk mempercepat-nya dengan satu atau lebih petanda tingkat-kedua. Teks mengisi citra, membebaninya dengan sebuah budaya, moral, imajinasi. Dulu, ada reduksi dari teks ke citra; sekarang teks mengeraskan atau memberi penjelasan tambahan atas citra. Konotasi sekarang dialami hanya sebagai gaung alamiah dari denotasi yang diberikan oleh analogi fotografis (teks). Dengan begitu, kita sekarang dihadapkan dengan proses tipikal dari naturalisasi budaya. Pesan parasitis dari foto yang dimuat di Kompas pada 2 Desember 2011 itu kuat berasal dari caption. Di caption itulah kita dibebani dengan sebuah budaya (pemukiman kumuh, infrastruktur yang buruk), moral (anak kecil harus menderita karena rob, apa yang harus kita lakukan?), dan imajinasi (seorang anak kecil yang berangkat ke sekolah, peta lokasi kejadian). Caption memberikan penjelasan tambahan yang dianggap diperlukan dalam sebuah foto jurnalistik yang dimuat di koran. Catatan kedua Barthes berkaitan dengan efek konotasi. Semakin dekat teks dengan citra, semakin kecil kemungkinan untuk mengkonotasikannya. Judul dan caption foto Rob di Kamal Muara adalah tipe teks yang seperti itu. Judul dan caption 4
datar, dibuat seakurat mungkin menjelaskan apa yang ada di foto. Tidak ada metafora, tidak ada permainan kata. Teks-teks itu tampak menduplikasi citra, dalam arti, bahwa teks itu dimasukkan ke dalam denotasinya. Tapi bagaimana mungkin teks menduplikasi citra? Itulah catatan ketiga Barthes. Dalam perpindahan dari struktur teks ke struktur citra, petanda-petanda tingkat-dua berkembang. Teks membuat konotasi citra lebih jelas (eksplisit) dan memberikan tekanan. Teks seringnya hanya memberi penjelasan mengenai konotasi-konotasi yang telah diberikan di dalam foto. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan lainnya adalah teks memproduksi atau menemukan petanda baru yang sepenuhnya berbeda yang kemudian diproyeksikan ke dalam citra. Di dalam judul dan caption foto Rob di Kamal Muara, kemungkinan pertama-lah yang terjadi. Teks-teks itu hanya memberikan penjelasan, tidak memproduksi petanda baru. Satu lagi konsep yang perlu dijabarkan berkaitan dengan foto, yakni apa yang disebut Roland Barthes sebagai citra traumatis (traumatic images). Apa itu citra traumatis? Apakah foto Rob di Kamal Muara merupakan citra traumatis? Trauma yang dimaksud di sini adalah penundaan atau penangguhan bahasa, perintangan makna. Di dalam foto, trauma sepenuhnya bergantung pada kepastian bahwa pemandangan itu sungguh-sungguh terjadi: fotografernya benar-benar di sana (definisi mitis dari konotasi). Mengasumsikan itu (berarti sudah konotasi), foto traumatis (kebakaran, kapal tenggelam, banjir, dll) adalah foto yang tentangnya tidak ada apa-apa yang bisa dikatakan lagi. Memang begitulah kejadiannya. Sedangkan foto-yang-mengguncang bersifat insignificant sehingga tidak ada nilai, tidak ada pengetahuan, tidak ada kategori verbal yang bisa melembagakan pemaknaannya. Semakin langsung trauma, semakin sulit konotasinya. Dengan melihat pembedaan foto traumatis dan foto-yang-mengguncang yang dibuat Roland Barthes, tampaknya foto Rob di Kamal Muara masuk kategori pertama. Rob memang seperti itu. Tidak ada yang mengguncang. Nilai, pengetahuan, dan kategori verbal masih bisa dilekatkan. Caption-nya berbicara tentang itu semua. Akan tetapi, masih ada yang mengganggu pikiran saya. Penjelasan Barhes tentang foto traumatis rasanya berbeda dengan penjelasan yang saya dapat di kelas perihal trauma fotografis. Yang saya tangkap, trauma fotografis terjadi ketika kita, pemandang atau pembaca foto, mendapatkan kebingungan (keliaran imajinasi tanpa batas) saat berhadapan dengan foto. Teks, biasanya judul atau caption, kemudian menyembuhkan trauma itu dengan membatasi keliaran. Dengan memakai pengertian trauma fotografis yang saya dapatkan itu, saya membayangkan bahwa hanya foto yang mampu memberikan trauma fotografis adalah foto-yangmengguncang, bukan foto traumatis. Namun, istilah trauma kemudian mengganggu saya. Sederhana saja: bukankah kita hanya akan mengalami trauma fotografis dari foto traumatis? Kenyataannya justru sebaliknya. Demikianlah uraian saya mengenai teori foto jurnalistik (dari Roland Barthes) dengan menggunakan rujukan foto Rob di Kamal Muara sebagai objek kajian. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tidak semua teori foto jurnalistik Roland Barhes bisa diaplikasikan ke foto itu. Dalam prosedur konotasi misalnya, kita tidak menemukan estetisisme dan sintaksis; konotasi foto utamanya terbangun melalui prosedur pose 5
dan objek; yang lainnya terbangun dari efek tipuan dan fotogenia. Teks dalam foto itu memberi penjelasan tambahan atas citra; karena teks foto sangat dekat dengan citra, maka teks itu tidak mengkonotasikan citra; teks itu hanya mengeksplisitkan konotasi yang sudah terbangun oleh citra. Dalam pembedaan Barthes tentang foto traumatis dan foto-yang-mengguncang, foto Rob di Kamal Muara merupaka foto traumatis.
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20013)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3272)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12945)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2506)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2565)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6516)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Dari EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9486)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5718)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDari EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspensePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1107)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDari EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5472)




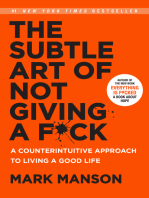





![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)