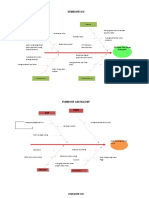Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
Diunggah oleh
Reza MelticaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
Diunggah oleh
Reza MelticaHak Cipta:
Format Tersedia
Nama NIM
: Reza Meltica : 12/335436/KU/15247
LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA WAWASAN NUSANTARA Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: "Britain rules the waves". Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat Wanus. Wanus ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengahtengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang: Satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hankam. Jelaslah disini bahwa Wanus adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan Wanus akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam "koridor" Wanus. A. Latarbelakang Berdasarkan Falsafah Pancasila. Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah : Makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak dan daya piker dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungan alamnya dan dengan Penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk: mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi demi terciptanya suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan demi terselenggaranya keteraturan dalam berhubungan dengan sesamanya. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sebenarnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari bangsa Indonesia termasuk dalam menggali dan mengembangkan wawasan nasional, hal ini dapat dilihat dalam sila-sila Pancasila.
B. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara. Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah. Kondisi obyektif geografis merupakan wadah atau ruang sebagai ruang gerak hidup suatu bangsa yang didalamnya terdapat Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu geografis merupakan fenomena yang mutlak diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tatalaku negara yang bersangkutan. Demikian juga sebaliknya, perlu diperhitungkan dampak sikap dan tatalaku negara terhadap geografis sebagai tata hubungan antara manusia dan wadah lingkungan. Kondisi Obyektif Geografis Nusantara Kondisi obyektif geografis nusantara merupakan untaian ribuan pulau-pulau yang tersebar dan terbentang di katulistiwa terletak pada posisi silang yang strategis, dengan watak atau karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Wilayah Indonesia Pada Saat Proklamasi 17 Agustus 1945. Masih berlaku TERRITORIALE ZEE EN MARITIEME KRINGEN ORDONANTIE TAHUN 1939. Dimana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pulau Indonesia. Penetapan lebar wilayah laut 3 mil ini, tidak menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bila dihadapkan dengan pergolakkan-pergolakkan yang terjadi di dalam negeri dan lingkungan keadaan alam). Atas pertimbangan tersebut maka keluarlah : * Yang menyatakan tentang penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Maka sejak itu berubahlah luas wilayah Indonesia dari: Kurang lebih 2 juta km persegi menjadi 5 juta km persegi. Dimana kurang lebih 65 % wilayahnya terdiri dari laut atau perairan (negara maritim), dan 35 % adalah daratan. Terdiri dari 17.508 buah pulau dengan 5 (lima) buah pulau besar : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya dan 11.808 pulau-pulau kecil yang belum diberi nama. Dengan luas daratan : kurang lebih 2.028.087 km persegi. Dengan panjang pantai : kurang lebih 81.000 km persegi. Topografi daratannya : merupkan pegunungan dengan gununggunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Jadi pengertian Nusantara adalah kepulauan indonesia yang terdiri dari 17.508 pulaupulau baik pulau besar dan pulau kecil dan diantara batas-batas astronomis sebagai berikut : - Utara : 06o08o lintang utara Selatan : 11o15olintang selatan - Barat : 94o45obujur barat Timur : 141o 05oderajad bujur timur Dengan jarak Utara Selatan : kurang lebih 1.888 km persegi. Jarak antara Barat Timur : kurang lebih 5.110 km persegi. Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional yang ke-3 Tahun 1982. Melalui konferensi tersebut maka pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention On The Law Of The Sea). Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang Undang No. 17 th 1985 pada tanggal 13 desember 1985. Berlakunya UNCLOS 1982, akan berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti , bertambah luasnya Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia (200 mil). UNCLOC 1982 memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional yaitu bertambah luasnya perairan
yuridiksi nasional berikut kekayaan alam yang terkandung dilaut dan dasar lautnya, serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut sebagai medium transportasi namun dari segi kerawanan juga bertambah. Perjuangan Indonesia selanjutnya menegakkan kedaulatan dirgantara terutama dalam rangka memanfaatkan wilayah Geo Stationery Orbit (GSO) yang dapat dijadikan wilayah kepentingan ekonomi maupun pertahanan dan keamanan negara dan bangsa Indonesia. C. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cipta, rasa dan karsa manusia (budi, perasaan dan kehendak). Sosio budaya sebagai salah satu aspek kehidupan nasional adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir dan batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara anggotanya. Masyarakat Indonesia, sejak awal terbentuknya dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam oleh pengaruh ruang hidup berupa kepulauan dengan ciri alamiah tiap-tiap pulau yang berbeda-beda pula. Disamping perbedaan ruang hidup, masyarakat Indonesia dibedakan pula dengan dasar Ras dan Etnik, yang memberikan perbedaan-perbedaan secara khas kebudayaan tiap daerah dan sekaligus menampakkan perbedaanperbedaan daya inderawi serta pola tingkah laku kehidupan baik dalam hubungan vertikal maupun horisontal. Dari ciri-ciri alamiah dapat dibedakan secara lahiriah : Orang Jawa, orang Batak, orang Madura, orang Dayak, orang Aceh dan sebagainya. Dari ciri-ciri ruang hidup (asalusul masyarakat) dapat dibedakan : Masyarakat nelayan dengan sifat pemberani, agresif, terbuka dan Masyarakat agraris dengan sifat teratur (mengikuti ritme alam), mementingkan keakraban, kurang terbuka. Masyarakat Desa dengan sifat religius, kekerabatan dan paguyuban, Masyarakat Kota dengan sifat materialistik, individual dan patembayan. Kebudayaan adalah warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang bersangkutan. Artinya generasi suatu masyarakat lahir dengan serta merta mewarisi norma-norma dari masyarakat sebelumnya. Warisan budaya tersebut diterima secara emosional dan mengikat ke dalan serta kuat, artinya ketersinggungan budaya (meskipun sepele) dapat memicu antar golongan masyarakat. Warisan budaya membentuk ikatan pada setiap individu atau masyarakat dengan daerah asal sehingga dapat membentuk sentimen-sentimen kelompok, suku, daerah asal (Parochial), yang seringkali dapat dijadikan sebagai perisai terhadap ketidakmampuan individu-individu atau kelompok masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang dianggap mengancam eksistensi budayanya. Berdasarkan ciri-ciri dan sifat-sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi NKRI, tergambar jelas : betapa heterogen dan uniknya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam prospektif budaya tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan masyarakat mengandung potensi konflik yang sangat besar. Terlebih dengan kesadaran nasional masyarakat Indonesia yang relatif masih rendah sejalan dengan masih terbatasnya jumlah masyarakat yang terdidik. Dari tinjauan sosio budaya tersebut pada akhirnya dapat dipahami bahwa Proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang segenap masyarakat, tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun mempunyai semangat untuk membina kehidupan
bersama yang harmonis. Sehingga Wawasan nasional atau wawasan kebangsaan indonesia diwarnai dengan keinginan untuk menumbuhsuburkan : Faktor positif : seperti terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Keinginan untuk mengurangi faktor negatif yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. D. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kesejarahan. Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-citanya pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat latarbelakang sejarah, demikian pula dengan sejarah Indonesia. Sebelum ada wilayah Nusantara, ada 2 kerajaan besar yang landasannya mewujudkan kesatuan wilayah (meskipun belum timbul rasa kebangsaan namun sudah ada semangat bernegara). Dua kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Dalam perjuangan berikutnya, nuansa kebangsaan mulai muncul sejak tahun 1900-an dengan konsep baru dan modern. Wujud konsep baru tersebut adalah lahirnya Proklamasi Kemerdekaan dan Proklamasi Penegakan Negara Merdeka.
PERKEMBANGAN WAWASAN NASIONAL INDONESIA Adapun kondisi obyektif geografi Indonesia telah mengalami perkembangan sebagai berikut : Saat RI merdeka (17 Agustus 1945), kita masih mengikuti aturan dalam Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 di mana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia. Dengan aturan itu maka wilayah Indonesia bukan merupakan kesatuan Laut menjadi pemisah-pemecah wilayah karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia kemudian mengeluarkan Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) berbunyi: berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman in bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titiktitik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Jadi, pulau-pulau dan laut di wilayah Indonesia merupakan satu wilayah yang utuh, kesatuan yang bulat dan utuh Indonesia kemudian mengeluarkan UU No 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang berisi konsep kewilayahan Indonesia menurut Deklarasi Djuanda itu maka Indonesia mempunyai konsep tentang Negara Kepulauan (Negara Maritim) Dampaknya: jika dulu menurut Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) tahun 1939 luas Indonesia adalah kurang lebih 2 juta km2 maka menurut Deklarasi Djuanda dan UU No 4/prp Tahun 1960 luasnya menjadi 5 juta km2 (dimana 65% wilayahnya terdiri dari laut/perairan) Pada 1982, Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional III mengakui pokokpokok asas Negara Kepulauan (seperti yang digagas menurut Deklarasi Djuanda). Asas
Negara Kepulauan itu diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law af the Sea). Dampak dari UNCLOS 1982 adalah pengakuan tentang bertambah luasnya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17 Tahun 1985 (tanggal 31 Desember 1985) Sejak 16 November 1993 UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara dan menjadi hukum positif sejak 16 November 1994. Perjuangan selanjutnya adalah perjuangan untuk wilayah antariksa nasional, termasuk GSO (Geo Stationery Orbit). Jadi wilayah Indonesia adalah (Prof. Dr. Priyatna dalam S. Sumarsono, 2005, hal 74): Wilayah territorial 12 mil dari Garis Pangkal Laut Wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil dari Pangkal Laut Wilayah ke dalam perut bumi sedalam 40.000 km Wilayah udara nasional Indonesia setinggi 110 km Batas antariksa Indonesia Tinggi = 33.761 km Tebal GSO (Geo Stationery Orbit) = 350 km Lebar GSO (Geo Stationery Orbit) = 150 km
Nama NIM
: Reza Meltica : 12/335436/KU/15247
LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA WAWASAN NUSANTARA Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: "Britain rules the waves". Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat Wanus. Wanus ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengahtengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang: Satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hankam. Jelaslah disini bahwa Wanus adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan Wanus akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam "koridor" Wanus. A. Latarbelakang Berdasarkan Falsafah Pancasila. Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah : Makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak dan daya piker dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungan alamnya dan dengan Penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk: mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi demi terciptanya suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan demi terselenggaranya keteraturan dalam berhubungan dengan sesamanya. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sebenarnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari bangsa Indonesia termasuk dalam menggali dan mengembangkan wawasan nasional, hal ini dapat dilihat dalam sila-sila Pancasila.
B. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara. Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah. Kondisi obyektif geografis merupakan wadah atau ruang sebagai ruang gerak hidup suatu bangsa yang didalamnya terdapat Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu geografis merupakan fenomena yang mutlak diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tatalaku negara yang bersangkutan. Demikian juga sebaliknya, perlu diperhitungkan dampak sikap dan tatalaku negara terhadap geografis sebagai tata hubungan antara manusia dan wadah lingkungan. Kondisi Obyektif Geografis Nusantara Kondisi obyektif geografis nusantara merupakan untaian ribuan pulau-pulau yang tersebar dan terbentang di katulistiwa terletak pada posisi silang yang strategis, dengan watak atau karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Wilayah Indonesia Pada Saat Proklamasi 17 Agustus 1945. Masih berlaku TERRITORIALE ZEE EN MARITIEME KRINGEN ORDONANTIE TAHUN 1939. Dimana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pulau Indonesia. Penetapan lebar wilayah laut 3 mil ini, tidak menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bila dihadapkan dengan pergolakkan-pergolakkan yang terjadi di dalam negeri dan lingkungan keadaan alam). Atas pertimbangan tersebut maka keluarlah : * Yang menyatakan tentang penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Maka sejak itu berubahlah luas wilayah Indonesia dari: Kurang lebih 2 juta km persegi menjadi 5 juta km persegi. Dimana kurang lebih 65 % wilayahnya terdiri dari laut atau perairan (negara maritim), dan 35 % adalah daratan. Terdiri dari 17.508 buah pulau dengan 5 (lima) buah pulau besar : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya dan 11.808 pulau-pulau kecil yang belum diberi nama. Dengan luas daratan : kurang lebih 2.028.087 km persegi. Dengan panjang pantai : kurang lebih 81.000 km persegi. Topografi daratannya : merupkan pegunungan dengan gununggunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Jadi pengertian Nusantara adalah kepulauan indonesia yang terdiri dari 17.508 pulaupulau baik pulau besar dan pulau kecil dan diantara batas-batas astronomis sebagai berikut : - Utara : 06o08o lintang utara Selatan : 11o15olintang selatan - Barat : 94o45obujur barat Timur : 141o 05oderajad bujur timur Dengan jarak Utara Selatan : kurang lebih 1.888 km persegi. Jarak antara Barat Timur : kurang lebih 5.110 km persegi. Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional yang ke-3 Tahun 1982. Melalui konferensi tersebut maka pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention On The Law Of The Sea). Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang Undang No. 17 th 1985 pada tanggal 13 desember 1985. Berlakunya UNCLOS 1982, akan berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti , bertambah luasnya Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia (200 mil). UNCLOC 1982 memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional yaitu bertambah luasnya perairan
yuridiksi nasional berikut kekayaan alam yang terkandung dilaut dan dasar lautnya, serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut sebagai medium transportasi namun dari segi kerawanan juga bertambah. Perjuangan Indonesia selanjutnya menegakkan kedaulatan dirgantara terutama dalam rangka memanfaatkan wilayah Geo Stationery Orbit (GSO) yang dapat dijadikan wilayah kepentingan ekonomi maupun pertahanan dan keamanan negara dan bangsa Indonesia. C. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cipta, rasa dan karsa manusia (budi, perasaan dan kehendak). Sosio budaya sebagai salah satu aspek kehidupan nasional adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir dan batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara anggotanya. Masyarakat Indonesia, sejak awal terbentuknya dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam oleh pengaruh ruang hidup berupa kepulauan dengan ciri alamiah tiap-tiap pulau yang berbeda-beda pula. Disamping perbedaan ruang hidup, masyarakat Indonesia dibedakan pula dengan dasar Ras dan Etnik, yang memberikan perbedaan-perbedaan secara khas kebudayaan tiap daerah dan sekaligus menampakkan perbedaanperbedaan daya inderawi serta pola tingkah laku kehidupan baik dalam hubungan vertikal maupun horisontal. Dari ciri-ciri alamiah dapat dibedakan secara lahiriah : Orang Jawa, orang Batak, orang Madura, orang Dayak, orang Aceh dan sebagainya. Dari ciri-ciri ruang hidup (asalusul masyarakat) dapat dibedakan : Masyarakat nelayan dengan sifat pemberani, agresif, terbuka dan Masyarakat agraris dengan sifat teratur (mengikuti ritme alam), mementingkan keakraban, kurang terbuka. Masyarakat Desa dengan sifat religius, kekerabatan dan paguyuban, Masyarakat Kota dengan sifat materialistik, individual dan patembayan. Kebudayaan adalah warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang bersangkutan. Artinya generasi suatu masyarakat lahir dengan serta merta mewarisi norma-norma dari masyarakat sebelumnya. Warisan budaya tersebut diterima secara emosional dan mengikat ke dalan serta kuat, artinya ketersinggungan budaya (meskipun sepele) dapat memicu antar golongan masyarakat. Warisan budaya membentuk ikatan pada setiap individu atau masyarakat dengan daerah asal sehingga dapat membentuk sentimen-sentimen kelompok, suku, daerah asal (Parochial), yang seringkali dapat dijadikan sebagai perisai terhadap ketidakmampuan individu-individu atau kelompok masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang dianggap mengancam eksistensi budayanya. Berdasarkan ciri-ciri dan sifat-sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi NKRI, tergambar jelas : betapa heterogen dan uniknya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam prospektif budaya tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan masyarakat mengandung potensi konflik yang sangat besar. Terlebih dengan kesadaran nasional masyarakat Indonesia yang relatif masih rendah sejalan dengan masih terbatasnya jumlah masyarakat yang terdidik. Dari tinjauan sosio budaya tersebut pada akhirnya dapat dipahami bahwa Proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang segenap masyarakat, tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun mempunyai semangat untuk membina kehidupan
bersama yang harmonis. Sehingga Wawasan nasional atau wawasan kebangsaan indonesia diwarnai dengan keinginan untuk menumbuhsuburkan : Faktor positif : seperti terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Keinginan untuk mengurangi faktor negatif yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. D. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kesejarahan. Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-citanya pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat latarbelakang sejarah, demikian pula dengan sejarah Indonesia. Sebelum ada wilayah Nusantara, ada 2 kerajaan besar yang landasannya mewujudkan kesatuan wilayah (meskipun belum timbul rasa kebangsaan namun sudah ada semangat bernegara). Dua kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Dalam perjuangan berikutnya, nuansa kebangsaan mulai muncul sejak tahun 1900-an dengan konsep baru dan modern. Wujud konsep baru tersebut adalah lahirnya Proklamasi Kemerdekaan dan Proklamasi Penegakan Negara Merdeka.
PERKEMBANGAN WAWASAN NASIONAL INDONESIA Adapun kondisi obyektif geografi Indonesia telah mengalami perkembangan sebagai berikut : Saat RI merdeka (17 Agustus 1945), kita masih mengikuti aturan dalam Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 di mana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia. Dengan aturan itu maka wilayah Indonesia bukan merupakan kesatuan Laut menjadi pemisah-pemecah wilayah karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia kemudian mengeluarkan Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) berbunyi: berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman in bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titiktitik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Jadi, pulau-pulau dan laut di wilayah Indonesia merupakan satu wilayah yang utuh, kesatuan yang bulat dan utuh Indonesia kemudian mengeluarkan UU No 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang berisi konsep kewilayahan Indonesia menurut Deklarasi Djuanda itu maka Indonesia mempunyai konsep tentang Negara Kepulauan (Negara Maritim) Dampaknya: jika dulu menurut Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) tahun 1939 luas Indonesia adalah kurang lebih 2 juta km2 maka menurut Deklarasi Djuanda dan UU No 4/prp Tahun 1960 luasnya menjadi 5 juta km2 (dimana 65% wilayahnya terdiri dari laut/perairan) Pada 1982, Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional III mengakui pokokpokok asas Negara Kepulauan (seperti yang digagas menurut Deklarasi Djuanda). Asas
Negara Kepulauan itu diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law af the Sea). Dampak dari UNCLOS 1982 adalah pengakuan tentang bertambah luasnya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17 Tahun 1985 (tanggal 31 Desember 1985) Sejak 16 November 1993 UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara dan menjadi hukum positif sejak 16 November 1994. Perjuangan selanjutnya adalah perjuangan untuk wilayah antariksa nasional, termasuk GSO (Geo Stationery Orbit). Jadi wilayah Indonesia adalah (Prof. Dr. Priyatna dalam S. Sumarsono, 2005, hal 74): Wilayah territorial 12 mil dari Garis Pangkal Laut Wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil dari Pangkal Laut Wilayah ke dalam perut bumi sedalam 40.000 km Wilayah udara nasional Indonesia setinggi 110 km Batas antariksa Indonesia Tinggi = 33.761 km Tebal GSO (Geo Stationery Orbit) = 350 km Lebar GSO (Geo Stationery Orbit) = 150 km
Anda mungkin juga menyukai
- Jadwal Pelatihan Pmba Periode IDokumen1 halamanJadwal Pelatihan Pmba Periode IReza MelticaBelum ada peringkat
- Tugas Agenda I Tata Cara ApelDokumen3 halamanTugas Agenda I Tata Cara ApelReza MelticaBelum ada peringkat
- Fishbone DS 2017Dokumen3 halamanFishbone DS 2017Reza MelticaBelum ada peringkat
- Literature ReviewDokumen2 halamanLiterature ReviewReza MelticaBelum ada peringkat
- EssayDokumen4 halamanEssayReza MelticaBelum ada peringkat
- Judi Dan PembunuhanDokumen9 halamanJudi Dan PembunuhanReza MelticaBelum ada peringkat
- Perhitungnan T-Girder JembatanDokumen23 halamanPerhitungnan T-Girder JembatanReza MelticaBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Ibm Sumber KarbohidratDokumen20 halamanLaporan Praktikum Ibm Sumber KarbohidratReza MelticaBelum ada peringkat