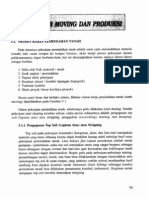Analisa Produktifitas Peledakan Untuk Mencapai Target Produksi Peledakan
Analisa Produktifitas Peledakan Untuk Mencapai Target Produksi Peledakan
Diunggah oleh
Lantang ElhyHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Analisa Produktifitas Peledakan Untuk Mencapai Target Produksi Peledakan
Analisa Produktifitas Peledakan Untuk Mencapai Target Produksi Peledakan
Diunggah oleh
Lantang ElhyHak Cipta:
Format Tersedia
Analisa Produktifitas Peledakan Untuk Mencapai Target Produksi
Peledakan
Pada sisitem tambang terbuka pembongkaran tanah penutup overburden dilakukan
dengan menggunakan metode pemboran (drilling) dan peledakan (blasting). Peledakan
pada kegiatan penambangan merupakan salah satu cara yang efektif untuk pemberaian
batuan yang secara fisik bersifat keras dan peledakan dilakukan agar proses
pemberaian batuan penutup terjadi secara singkat dan waktu yang digunakan pun
cukup cepat. Dalam suatu kegiatan peledakan (blasting), fragmentasi dan pelemparan
batuan (flyrock) adalah merupakan dua akibat mendasar dari kegiatan peledakan yang
harus diperhatikan. Salah satu penilaian terhadap keberhasilan suatu operasi peledakan
pada areal tambang adalah tercapainya suatu tingkat fragmentasi batuan sesuai dengan
yang direncanakan. Pada perusahaan tambang fragmentasi batuan hasil peledakan
yang dibutuhkan harus sesuai dengan kapasitas alat muat dan alat angkut yang akan
digunakan setelah proses peledakan tersebut.
A. Landasan Teori dan Metodologi Pemecahan Masalah
1. Landasan Teori
a. Klasifikasi Batuan
Berdasarkan kejadian dari batuan, batuan dibagi menjadi golongan :
1) Batuan Beku
Batuan beku terjadi dari pembekuan magma yang mengalami proses pendinginan dan
membentuk kristal secara perlahan-lahan.
2) Batuan Sedimen Batuan sedimen terbentuk dari proses pengendapan material-
material hasil pelapukan yang tersusun secara berlapis menurut urutan waktu
pengendapan.
3) Batuan Metamorf
Batuan metamorf terjadi dari suatu proses rekristalisasi yang terjadi pada temperatur
dan tekanan yang tinggi. Sifat-sifat dari batuan yang dihasilkan tergantung pada batuan
yang terkena metamorfosa dan seberapa jauh deformasi yang berhubungan dengan
prosesnya.
b. Sifat-sifat Teknis Batuan Sebelum melakukan kegiatan peledakan, seorang juru ledak
harus mengetahui sifat-sifat teknis batuan yang akan dilakukan peledakan karena hal
tersebut akan mempengaruhi kegiatan pemboran untuk lubang ledak tersebut. Sifat-sifat
teknis batuan itu terdiri dari: (Sumber ; Diktat Supevisory Teknik Peledakan, Diklat
Angkatan VI, Pt Karimun Granit-Riau 1996)
1) Kekerasan
Kekerasan merupakan daya tahan dari suatu bidang permukaan halus abrasinya.
Kekerasan batuan dapat juga digunakan untuk menyatakan besarnya tegangan yang
menyebabkan kerusakan batuan. Ciri-cirinya yaitu: (a) padat, (b) kuat, dan (c) tidak
mudah pecah.
2) Tekstur Tekstur dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat looseness, density, porositas
dan ukuran butir.
3) Abrasivitas Abrasivitas yaitu pengikisan oleh gesekan antara dua material yang
mempeunyai daya hancur, atau merupakan suatu parameter yang mempengaruhi
keausan mata bor (drill bit) dan batang bor (drill stell). Untuk menghitung untuk
mengukur keausan mata bor abrasivitas tergantung pada komposisi batuan yang
terkandung didalam batuan tersebut.
4) Rock drill ability Rock drill ability adalah kecepatan penetrasi mata bor kedalam
batuan.
5) Rock blast ability Rock blast ability merupakan tahanan terhadap peledakan yang
sangat dipengaruhi oleh keadaan batuan. Batuan yang keras dan padat pada kegiatan
peledakan dapat dikontrol dengan baik. Sedangkan pada batuan yang banyak terdapat
celah, sebagian energi dari bahan peledak akan hilang kedalam rekahan dan proses
peledakan akan sulit dikontrol. Adapun faktor yang mempengaruhi Rock Blast Ability
antara lain: (a) patahan, (b) jenis batuan, (c) bidang perlapisan, dan (d) strike-dip
formasi batuan.
c. Mekanisme Pecahnya Batuan Akibat Peledakan Konsep yang dipakai adalah konsep
pemecahan dan reaksireaksi mekanik dalam batuan homogen. Sifat mekanis dalam
batuan yang homogen akan berbeda dari batuan yang mempunyai rekahanrekahan
heterogen seperti yang dijumpai dalam pekerjaan peledakan. Proses pecahnya batuan
akibat dari peledakan dibagi dalam tiga proses yaitu: (a) dynamic loading,(b) quasi-static
loading, dan (c) release of loading (Sumber ; Diktat Kuliah Teknik Peledakan, UNP).
1) Proses pemecahan tingkat I (Dynamic Loading) Pada saat bahan peledak meledak,
tekanan tinggi menghancurkan batuan di daerah sekitar lubang ledak. Gelombang kejut
yang mengakibatkan lubang ledak merambat dengan kecepatan 9000 17000 ft/det
akan mengakibatkan tegangan tangensial, yang menimbulkan rekahan yang menjalar
dari daerah lubang ledak. Rekahan pertama menjalar terjadi dalam waktu 1 - 2 ms.
Pada tahap ini terjadi penghancuran batuan disekitar lubang tembak dan energi ledakan
diteruskan kesegala arah.
2) Proses pemecahan tingkat II (Quasi-static Loading) Tekanan sehubungan dengan
gelombang kejut yang meninggalkan lubang ledak pada proses pemecahan tingkat I
adalah positif. Apabila mencapai bidang bebas akan dipantulkan, tekanan akan turun
dengan cepat, kemudian berubah menjadi negatif dan timbul gelombang tarik.
Gelombang tarik ini merambat kembali di dalam batuan. Oleh karena itu batuan lebih
kecil ketahanannya terhadap tarikan dari pada tekanan, maka akan terjadinya rekahan-
rekahan primer yang disebabkan karena tegangan tarik dari gelombang yang
dipantulkan. Apabila tegangan renggang cukup kuat, akan menyebabkan slambing atau
spalling pada bidang bebas. Dalam proses pemecahan tingkat I dan II, fungsi dari
gelombang kejut adalah menyiapkan batuan dengan sejumlah rekahan-rekahan kecil.
Secara teoritis energi gelombang kejut jumlahnya berkisar antara 5 15 % dari energi
total bahan peledak. Jadi gelombang kejut menyediakan kesiapan dasar untuk proses
pemecahan tingkat akhir. Pada tahap ini energi ledakan yang bergerak sampai bidang
bebas menghancurkan batuan pada dinding jenjang tersebut.
3) Proses pemecahan tingkat III (release of loading) Dibawah pengaruh tekanan yang
sangat tinggi dari gas-gas hasil peledakan maka rekahan radial primer (Tingkat II) akan
diperlebar secara cepat oleh kombinasi efek dari tegangan tarik yang disebabkan
kompresi radial dan pembagian (pneumetic wedging). Apabila massa batuan didepan
lubang ledak gagal dalam mempertahankan posisinya bergerak kedepan maka
tegangan tekan tinggi yang berada dalam batuan akan dilepaskan. Efek dari terlepasnya
batuan adalah menyebabkan tegangan tarik tinggi dalam massa batuan yang akan
melanjutkan pemecahan hasil yang telah terjadi pada proses pemecahan tingkat II.
Rekahan hasil dalam pemecahan tingkat II menyebabkan bidang-bidang lemah untuk
memulai reaksi-reaksi frakmentasi utama pada proses peledakan. Pada tahapan
terakhir ini energi yang dipantulkan oleh bidang bebas pada tahap sebelumnya akan
mengahancurkan batuan dengan lebih sempurna.
(sumber ; Laporan, Data-data dan Arsip PT. Nusa Alam Lestari)
Gambar 1. Proses Pecahnya Batuan Akibat Peledakan
d. Fragmentasi Batuan Fragmentasi adalah istilah umum untuk menunjukkan ukuran
setiap bongkah hasil peledakan. Ukuran fragmentasi tergantung pada proses
selanjutnya. Untuk tujuan tertentu ukuran fragmentasi batuan yang besar (boulder)
diperlukan, misalnya disusun sebagai penghalang di tepi jalan tambang. Namun
kebanyakan diinginkan ukuran fragmentasi yang kecil karena penanganan pada
kegiatan selanjutnya akan lebih mudah. Ukuran fragmentasi terbesar biasanya dibatasi
oleh dimensi mangkok alat gali (excavator atau shovel) yang akan memuatnya ke
dumptruck.
Beberapa ketentuan umum tentang hubungan fragmentasi denagn lubang ledak :
1) Ukuran lubang ledak yang besar akan menghasilkan bongkahan fragmentasi, oleh
karena itu harus dikurangi dengan menggunakan bahan peledak yang lebih kuat.
2) Perlu diperhatikan bahwa dengan menambah bahan peledak akan menghasilkan
lemparan yang jauh.
3) Pada batuan dengan intensitas retakan tinggi dan jumlah bahan peledak sedikit
dikombinasikan dengan jarak spasi pendek akan menghasilkan fragmentasi kecil.
e. Pengaruh Ledakan Terhadap Batuan Pengaruh ledakan yang dilakukan
menyebabkan timbulnya : daerah hancuran, daerah retakan, getaran tanah (ground
vibration), dan air blast.
1) Daerah Hancuran Daerah hancur (crushed zone) terdapat di sekitar lubang ledak,
dimana batuan padat akan berubah menjadi butiran-butiran halus berupa serbuk. Hal ini
dikarenakan tingginya temperatur dan tekanan gas gas hasil reaksi peledakan serta
tingginya tekanan detonasi. Ukuran daerah ini tergantung pada jenis bahan peledak dan
material yang akan diledakkan.
2) Daerah Retakan Daerah retakan (fracture zone) terjadi jika tegangan yang
ditimbulkan oleh ledakan lebih besar dari tegangan yang dapat diterima batuan.
Retakanretakan yang terbentuk pertama kali disebabkan oleh tekanan detonasi yang
kemudian diperbesar oleh tekanan peledakan. Ukuran daerah ini dipengaruhi oleh jenis
batuan dan bahan peledak. Untuk batuan sedimen ukuran daerah retakan dapat
mencapai 40 kali diameter lubang ledak.
3) Getaran Tanah Getaran tanah (ground vibration) terjadi pada daerah elastic (elstic
zone). Di daerah ini tegangan yang diterima batuan lebih kecil dari kekuatan batuan
sehingga hanya menyebabkan perubahan bentuk dan volume. Sesuai dengan sifat
elastic batuan maka bentuk dan volumenya akan kembali kekeadaan semula setelah tak
ada tegangan yang bekerja. Perambatan tegangan pada daerah elastic akan
menimbulkan gelombang elastic yang dikenal juga sebagai gelombang seismic.
4) Air blast. Air blast adalah gelombang tekanan yang dirambatkan di atmosfer dengan
kecepatan diatas kecepatan suara. Ada dua macam air blast :
a) Yang dapat didengar (audible sound)
b) Yang tidak dapat didengar (subaudible sound)
Audible air blast mempunyai frekuensi dibawah 29 Hz.
f. Faktor Yang Mempengaruhi Fragmentasi Batuan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi fragmentasi bantuan dari hasil peledakan adalah :
1) Karakteristik batuan
Karakteristik batuan dapat berupa :
a) Kekuatan (strenght).
Strenght merupakan kekuatan batuan untuk menahan beban atau gaya yang bekerja
pada batuan tanpa terjadi kerusakan pada batuan. Gaya-gaya tersebut berupa gaya
tarik dan gaya tekan.
b) Kekerasan Kekerasan adalah tahanan dari suatu bidang permukaan halus terhadap
abrasi. Kekerasan dipakai untuk mengukur sifat-sifat teknis dari material batuan dan
dapat juga dipakai untuk menyatakan berapa besarnya tegangan yang diperlukan untuk
menyebabkan kerusakan pada batuan.
c) Kerapatan (density) Batuan yang mempunyai kerapatan yang tinggi berarti
mempunyai butiran rapta dan padat sehingga memungkinkan penyebaran energi dalam
batuan lebih mudah dan cepat. Batuan yang paling rapat mempunyai kehilangan energi
yang lebih kecil dan cenderung dapat hancur lebih baik.
d) Kecepatan Penyebarab Energi (velocity) Kecepatan penyebaran energi atau velocity
batuan dapat diartikan sebagai waktu yang diperlukan energi tekan sampai ke bidang
bebas dan kemudian kembali lagi.
e) Elastisitas Sifat elastisitas batuan dapat dinyatakan dalam modulus elastisitas.
Modulus elastisitas merupakan faktor kesebandingan antara tegangan normal dan
regangan relatifnya. Modulus elastisitas sangat tergantung pada komposisi mineralnya,
porositas, jenis perpindahan dan beban yang diterapkan.
f) Plastisitas Plastisitas batuan merupakan perilaku batuan yang menyebabkan
deformasi tetap setelah tegangan dikembalikan ke kondisi awal, dimana batuan tersebut
belum hancur.
2) Struktur geologi Stuktur geologi batuan dapat mempengaruhi kelurusan lubang ledak
dan kecepatan pemboran. Sedangkan pada proses peledakan struktur geologi dapat
melemahkan gelombang kejut dan melepaskan serta membuat ketidakseimbangan
dalam distribusi isian bahan peledak.
3) Pengaruh air tanah Kondisi air tanah juga dapat mempengaruhi hasil dari peledakan.
Adanya air tanah dapat menyebabkan terjadinya pendinginan reaksi dan larutnya unsur-
unsur bahan peledak oleh air.
Bahan peledak ANFO (Ammonium Nitrat-Fuel Oil) memiliki tingkat ketahanan yang
buruk terhadap air, sehingga apabila ANFO yang digunakan terkontaminasi oleh air
maka akan mempengaruhi fragmentasi batuan hasil peledakan bahkan bisa
menyebabkan terjadinya gagal ledak (misfire).
4) Geometri Pemboran Geometri Pemboran dan pola pemboran dirancang secara
terpadu dalam rancangan peledakan. Geometri pemboran meliputi : diameter lubang
bor, burden, spasi, kedalaman lubang bor dan kemiringan.
Geometri pemboran juga meliputi arah pemboran. Arah pemboran ada dua yaitu : arah
pemboran tegak dan arah pemboran miring. Lubang tembak yang dibuat tegak, maka
pada bagian lantai jenjang akan menerima gelombang tekan yang besar, sehingga
menimbulkan tonjolan (toe) pada lantai jenjang, hal ini dikarenakan gelombang tekan
sebagian akan dipantulkan pada bidang bebas dan sebagian lagi akan diteruskan pada
bagian bawah lantai jenjang. Dan energi pada peledakan ini juga tidak cukup untuk
memberikan dorongan untuk melepas batuan dari batuan induknya. Sedangkan dalam
pemakaian lubang tembak miring akan membentuk bidang bebas yang lebih luas,
sehingga akan mempermudah proses pecahnya batuan karena gelombang tekan yang
dipantulkan lebih besar dan gelombang tekan yang diteruskan pada lantai jenjang lebih
kecil. Kemiringan lobang tembak sebenarnya tergantung pada lokasi peledakan
dilapangan.
(Sumber : Arsip-arsip bagian pemboran PT. Nusa Alam Lestari)
Gambar 2. Arah Pemboran
5) Pola Pemboran
Keberhasilan suatu peledakan salah satunya terletak pada ketersediaan bidang bebas
yag mencukupi. Pola pemboran merupakan suatu pola pada kegiatan pemboran dengan
mendapatkan lobang-lobang tembak secara sistematis. Pola pemboran yang bisa
diterapkan pada tambang terbuka bisaanya ada tiga macam pola pemboran yaitu:
a) Pola Bujur Sangkar (square pattern) Pola pemboran ini adalah dimana jarak antara
burden dan spasi nya sama panjang yang membentuk bujursangkar.
b) Pola Persegi Panjang (rectangular pattern) Pola pemboran persegi panjag dimana
ukuran spacing dalam satu baris lebih besar dari jarak burden yang membentuk pola
persegi panjang. Untuk mendapatkan fragmentasi yang baik, pola ini kurang tepat
karena daerah yang tidak terkena pengaruh peledakan cukup besar.
(Sumber : Arsip-arsip bagian pemboran PT. Nusa Alam Lestari)
Gambar 3. Pola pemboran square pattern dan rectangular pattern
c) Pola selang-seling (staggered pattern) Dalam pemboran selang seling lobang tembak
dibuat seprti zig zag sehingga membentuk pola segi tiga. Dimana jarak spacing besar
sama atau lebih besar dari pada jarak burden. Pada pola ini daerah yang tidak terkena
pengaruh peledakan cukup kecil dibandingkan dengan pola yang lainya. Namun pada
penerapan dilapangan pola ini cukup sulit melakukan pemboran dan pengaturan lebih
lanjut. Tetapi untuk menperbaiki fragmentasi batuan hasil peledakan maka pola ini lebih
cocok untuk digunakan. (sumber ; diktat pelaksanaan peledakan pada kegiatan
penambangan bahan galian)
Gambar 4. keuntungan pola pemboran selang-seling
Untuk mendapatkan fragmentasi hasil peledakan yang baik, pola pemboran juga harus
diperhatikan. Karena, terlihat jelas pada gambar 24 area tidak terkena energi peledakan
lebih kecil dibandingkan pola pemboran sejajar. Dimana pada area tidak terkena energi
peledakan, batuan tersebut akan berurukan besar atau dapat dikatakan fragmentasi
hasil peledakan berukuran besar (boulder).
g. Peledakan Peledakan pada perusahaan tambang dilakukan untuk memberaikan
batuan dari batuan induknya. Dan dilakukan untuk menunjang operasi penggalian yang
dilakukan excavator, karna tujuan dari peledakan itu sendiri membuat fragmentasi
sehingga dapat menghasilkan rekahan pada batuan, yang dapat memudahkan dalam
proses penggalian batuan tersebut.
1) Geometri Peledakan Geometri peledakan merupakan suatu hal yang sangat
menentukan hasil peledakan dari segi fragmentasi yang dihasilkan, rekahan yang
diharapkan maupun dari segi jenjang yang terbentuk.
Dalam kegiatan peledakan, yang termasuk geometri peledakan adalah : burden, spasi,
stemming, subdrilling, kedalaman lubang ledak, panjang kolom isisan, diameter lubang
ledak dan tinggi jenjang.
(sumber ; http;//geometripeledakanimage.com)
Gambar 5. Geometri peledakan
a) Burden (B) Burden merupakan jarak tegak lurus antara lubang tembak terhadap
bidang bebas yang paling dekat. Burden merupakan dimensi yang paling penting dalam
kegiatan peledakan, karna burden digunakan untuk menentukan geometri peledakan
lainnya. Jarak burden yang baik adalah jarak yang memungkinkan energi secara
maksimal dapat bergerak keluar dari kolom isian menuju bidang bebas dan dipantulkan
kembali dengan kekuatan yang cukup untuk melampaui kuat tarik batuan sehingga akan
terjadi penghancuran. Apabila peledakan dilakukan dengan penerapan jarak burden
yang terlalu kecil maka akan mengakibatkan energi ledakan dengan mudah bergerak
menuju bidang bebas dapat menyebabkan terjadinya batuan terbang (flying rock).
Sedangkan jarak burden yang terlalu besar akan mengaskibatkan energi tidak cukup
kuat untuk mencapai bidang bebas sehingga pecahnya batuan akan terbentuk
bongkahan atau (boulder)
b) Spasi (S) Spasi adalah jarak antara lubang tembak dalam satu baris dan diukur
sejajar terhadap dinding teras (jenjang). Dalam memperkirakan panjang spasi, yang
perlu diperhatikan adalah apakah ada interaksi antara charges yang berdekatan.
Apabila masing masing lubang bor diledakan sendiri sendiri dengan interval waktu
yang cukup panjang dan untuk memungkinkan setiap lubang bor meledak dengan
sempurna, maka tidak akan terjadi interaksi antar gelombang energi masing masing.
Tetapi kalau waktu tunda diperpendek maka akan terjadi interaksi, sehingga akan
menyebabkan terjadinya efek yang kompleks.
c) Stemming (T) Stemming atau collar merupakan suatu kolom untuk tempat material
penutup di dalam lubang tembak yang terletak di atas kolom isian.Stemming digunakan
untuk menentukan stress balance (Tegangan untuk memecah batuan agar dapat
meledak keatas dan kesamping secara serentak). Stemming juga berguna untuk
mengurung gas gas yang timbul dari hasil peledakan sehingga dapat merekahkan
batuan dengan energi yang maksimal. Ada dua hal yang berhubungan dengan
stemming antara lain :
(1) Ukuran panjang stemming Ukuran panjang stemming pada umumnya sama dengan
burden apabila peledakan dilakukan pada batuan yang kompak, untuk mendapatkan
hasil peledakan yang maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila didalam
proses peledakan menggunakan panjang stemming yang terlalu pendek maka energi
ledakan yang dihasilkan cenderung lebih cepat mencapai bidang bebas sehingga
menimbulkan batuan terbang (fly rock) dan energi yang menekan batuan tidak
maksimal. Stemming yang pendek juga akan menghasilkan fragmentasi batuan yang
kurang baik. Sebaliknya apabila panjang stemming telalu panjang dapat menyebabkan
energi ledakan terkurung secara sempurna sehingga energi ledakan tidak sampai ke
permukaan lubang tembak yang dapat menyebabkan terjadinya bongkahan-bongkahan
pada permukaan lubang tembak.
(2) Ukuran material stemming Ukluran material stemming sangat berpengaruh terhadap
hasil peledakan, apabila bahan stemming terdiri dari butiran-butiran halus hasil
pemboran (cutting), kurang memiliki gaya gesek terhadap lubang tembak sehingga
udara yang bertekanan tinggi akan mudah mendorong material stemming tersebut.
Sehingga energi yang seharusnya untuk menghancurkan batuan, banyak hilang melalui
rongga stemming. untuk mencegahnya banyak menggunakan bahan yang berbutir
kasar dan keras.
(sumber ; http;//geometripeledakanimage.com)
Gambar 6. stemming
d) Subdrilling (J) Subdrilling merupakan penambahan kedalaman pada lubang ledak
dengan tujuan supaya batuan dapat meledak secara full face sebagaimana yang
diharapkan dan batuan yang terbongkar hanya sebatas lantai jenjang saja. Subdrilling
yang terlalu pendek dapat mengakibatkan terjadinya tonjolan (toe) sehingga dapat
menyulitkan proses kegiatan selanjutnya.
e) Kedalaman lubang ledak (H) Kedalaman lobang ledak merupakan kedalaman lobang
yang akan diledakan yang merupakan penjumlahan antara tinggi jenjang dengan
subdrilling. Kedalaman lobang ledak yang dibuat tidak boleh lebih kecil dari pada
burden. Hal ini bertujuan untuk menghidari tejadinya (overbreak) dan (fly rock).
Kedalaman lobang ledak bisaanya ditentukan berdasarkan kapasitas produksi yang
diinginkan.
(sumber ; http;//geometripeledakanimage.com)
Gambar 7. Kedalaman lubang ledak
f) Tinggi jenjang (L) Secara spesifik tinggi jenjang maksimum ditentukan oleh peralatan
lobang bor dan alat muat yang tersedia. Tinggi jenjang diambil berdasarkan kedalaman
lobang tembak dan subdrilling. Jika tinggi jenjang melebihi kedalaman lobang tembak,
maka sering terbentuknya tojolan (toe) dibagian bawah jenjang. Hal ini desebabkan
karena energi ledak dari bahan peledak tidak mampu mencapai bagian bawah jenjang.
g) Panjang kolom isian (PC) Panjang kolom isian merupakan panjang kolom lobang
tembak yang akan diisi bahan peledak. Panjang kolom ini merupakan kedalaman lobang
tembak dikurangi stemming yang digunakan. Semakin banyak bahan peledak yang
digunakan dalam proses peledakan maka akan memerlukan panjang kolom isian yang
cukup panjang sehingga juga akan berpengaruh kepada ukuran panjang stemming.
(sumber ; diktat pelaksanaan peledakan pada kegiatan penambangan bahan galian)
Gambar 8. Panjang kolom isian (PC)
2) Pola peledakan Secara umum pola peledakan menunjukkan urutan ledakan dari
sejumlah lubang ledak. Adanya urutan peledakan berarti terdapat jeda waktu ledakan
diantara lubang-lubang ledak yang disebut waktu tunda (delay time). Berikut ini adalah
keuntungan yang diperoleh dengan menerapkan waktu tunda pada sistem peledakan
antara lain :
a) Mengurangi getaran
b) Mengurangi over break dan batuan terbang (fly rock)
c) Mengurangi gegaran akibat air blast dan suara (noise)
d) Dapat mengarahkan lemparan fragmentasi batuan
e) Dapat memperbaiki ukuran fragmentasi batuan hasil peledakan
Berdasarkan arah runtuhan batuan, pola peledakan diklasifikasikan sebagai berikut :
a) Box cut Box cut adalah pola peledakan yang arah runtuhan batuannya kedepan dan
membentuk kotak
b) Corner cut Corner cut adalah pola peledakan yang arah runtuhan batuannya ke salah
satu sudut dari bidang bebas
c) V cut V cut adalah pola peledakan yang arah runtuhan batuannya kedepan dan
membentuk huruf V.
h. Klasifikasi Bahan Peledak
Bahan peledak pada industri pertambangan pada umumnya terbuat dari campuran
bahan-bahan kimia, sehingga disebut bahan peledak kimia. Defenisi dari bahan peledak
adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas
atau campurannya yang apabila diberi aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awal
akan bereaksi dengan sangat cepat dan bersifat panas (eksotermis) yang hasil
reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas bertekanan tinggi dan temperatur
yang sangat panas. Peledakan akan memberikan hasil yang berbeda dari yang
diharapkan karena tergantung pada kondisi eksternal saat pekerjaan tersebut dilakukan
yang mempengaruhi kualitas bahan kimia pembentuk bahan peledak tersebut. Panas
merupakan awal terjadinya proses dekomposisi bahan kimia pembentuk bahan peledak
yang menimbulkan pembakaran, dilanjutkan dengan deflagrasi dan terakhir detonasi.
Proses dekomposisi bahan peledak dapat diuraikan sebagai berikut : (sumber ; diktat
pelaksanaan peledakan pada kegiatan penambangan bahan galian)
1) Pembakaran
Pembakaran adalah reaksi kimia yang bersifat panas pada permukaan objek yang
terbakar dan dijaga keberlangsungan proses pembakarannya oleh panas yang
dihasilkan dari reaksi itu sendiri dan produknya berupa gas-gas. Reaksi pembakaran
memerlukan unsur oksigen baik yang terdapar di alam bebas maupun dari ikatan
molekul bahan ataupun material yang terbakar.
2) Deflagrasi
Deflagrasi adalah reaksi pembakaran dengan kecepatan sangat tinggi dan
menghasilkankan gas-gas bertekanan yang tekananya meningkat (ekspansi) selama
proses pembakaran berlangsung, sehingga menimbulkan ledakan. Akibat dari tekanan
ini, maka terjadi efek pengangkatan yang besarnya sebanding dengan proses
pembakaran yang terjadi. 3) Ledakan
Ledakan adalah ekspansi seketika yang cepat dari gas menjadi bervolume lebih besar
dan diiringi suara keras serta efek mekanis yang merusak. Dari defenisi tersebut tersirat
bahwa ledakan tidak melibatkan reaksi kimia, tapi kemunculannya disebabkan oleh
transfer energi ke gerakan massa yang menimbulkan efek mekanis yang merusak
disertai panas dan bunyi yang keras.
4) Detonasi
Detonasi adalah proses kimia-fisika dengan kecepatan reaksi yang sangat tinggi yang
menghasilkan gas dan temperatur sangat besar serta membangun ekspansi gaya yang
sangat besar pula. Kecepatan reaksi tersebut menyebarkan tekanan panas ke seluruh
zona peledakan dalam bentuk gelombang tekan kejut (shock compression wave) dan
proses ini berlangsung terus menerus untuk membebaskan energi hingga berakhir dan
memberikan efek merusak (shattering effect).
Bahan peledak diklasifikasikan berdasarkan sumber energinya menjadi bahan peledak
mekanik, kimia dan nuklir. Jenis bahan peledak secara garis besar diklasifikasikan
menjadi 3 golongan (menurut JJ manon 1978) adalah : (sumber; Diktat Pelaksanaan
Peledakan Pada Kegiatan Penambangan Bahan Galian, Khursus Juru Ledak 2011)
1) Bahan peledak mekanis
2) Bahan peledak kimia
a) High explosive : primary explosive dan secondary explosive
b) Low explosive : permissible exposive dan non permissible explosive
3) Bahan peledak nuklir
i. Sifat Fisik Bahan Peledak
sifat fisik bahan peledak merupakan suatu kenampakan nyata dari sifat bahan peledak
ketika menghadapi perubahan kondisi lingkungan sekitarnya. Kenampakan nyata inilah
yang harus diamati dan diketahui tanda-tandanya oleh seorang juru ledak untuk
mengidentifikasi suatu bahan peledak yang rusak, rudak tapi masih bisa dipakai, dan
tidak rusak. Sifat fisik bahan peledak yang harus diperhatikan adalah : (sumber; Diktat
Pelaksanaan Peledakan Pada Kegiatan Penambangan Bahan Galian, Khursus Juru
Ledak 2011)
1) Densitas
Densitas secara umum adalah angka yang menyatakan perbandingan berat per volume
2) Sensitivitas
Sensitivitas adalah sifat yang menunjukkan tingkat kemudahan atau kerentanan suatu
bahan peledak untuk terinisiasi (meledak) akibat adanya dorongan dari luar dalam
bentuk benturan (impact), gelombang kejut (shock wave), panas (flame), atau gesekan
(friction).
3) Ketahanan Terhadap Air (water resistance) Ketahanan bahan peledak terhadap air
adalah ukuran kemampuan suatu bahan peledak untuk melawan air disekitarnya tanpa
kehilangan sensitivitas. Apabila suatu bahan peledak larut dalam air dalam waktu yang
pendek berarti bahan peledak tersebut mempunyai ketahanan terhadap air yang buruk,
sebaliknya bila tidak larut dalam air disebut sangat baik (exellent). Contoh bahan
peledak yang mempunyai ketahan terhadap air yang buruk adalah ANFO (Ammonium
Nitrat, Fuel Oil), sedangkan bahan peledak yang mempunyai ketahanan terhadap air
yang sangat baik adalah emulsi, watergel, slurries.
4) Kestabilan Kimia (chemical stability) Kestabilan kimiabahan peledak adalah
kemampuan untuk tidak berubah secara kimia dan tetap mempertahankan sensitivitas
selama dalam penyimpanan di dalam gudang dengan kondisi tertentu. Faktor-faktor
yang mempercepat ketidak stabilan kimiawi antara lain panas, dingin, kelembaban,
kualitas bahan baku, kontaminasi, pengepakan dan fasilitas gudang bahan peledak.
5) Karakteristik Gas (fumes characteristic) Detonasi bahan peledak akan menghasilkan
fume, yakni gas hasil peledakan yang mengandung racun (toxic), apabila proses
pencampuran ramuan bahan peledak tidak sempurna yang menyebabkan terjadinya
kelebihan atau kekurangan oksigen selama proses dekomposisi kimia bahan peledak
berlangsung. Gas hasil peledakan yang tergolong fume antara lain nitrogen monoksida
(NO), nitrogen oksida (NO2), dan karbon monoksida (CO).
Sangat diharapkan dari detonasi suatu bahan peledak komersial tidak menghasilkan
gas-gas beracun, namun kenyataannya di lapangan hal tersebut sulit dihindari akibat
beberapa faktor antara lain :
a) Pencampuan ramuan bahan peledak yang meliputi unsur oksida dan bahan bakar
tidak seimbang, sehingga tidak mencapai zero oxygen balance
b) Letak primer tidak tepat
c) Kurang tertutup karna pemasangan stemming kurang padat dan kuat
d) Adanya air dalam lubang ledak
e) Sistem waktu tunda (delay time system) tidak tepat
f) Kemungkinan adanya reaksi antarabahan peledak dengan batuan.
2. Metodologi Pemecahan Masalah
a. Pengisian bahan peledak
1) Powder faktor (PF)
Powder faktor merupakan suatu bilangan untuk menyatakan jumlah material yang
diledakkan atau dibongkar oleh sejumlah bahan peledak yang dapat dinyatakan dalam
kg/ton. (Raimon Kopa) Pf biasanya sudah ditetapkan oleh perusahaan karena
merupakan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya dan juga karna berbagai
pertimbangan.
2) Panjang kolom isian (PC) Panjang kolom isian adalah kedalaman lubang ledak
dikurangi stemming. (sumber : diktat kuliah teknik peledakan, UNP)
PC = H T
Keterangan :
Pc = Panjang Kolom Isian (m)
H = Kedalaman Lubang (m)
T = Stemming (m)
3) Bahan Peledak ANFO
Dalam penggunaan ANFO sesuai dengan ketentuan Zero Oxygen Balance maka
perbandingan yang digunakan adalah 94,5 % Amonium Nitrat (AN) dan 5,5 % Fuel Oil
(FO). (sumber ; Diktat Pelaksanaan Peledakan Pada Kegiatan Penambangan Bahan
Galian, Khursus Juru Ledak 2011)
4) Loading Density Loading Density merupakan banyaknya bahan peledak untuk setiap
panjang kolom lubang ledak yang dinyatakan dalam kg/m. (sumber : diktat kuliah teknik
peledakan, UNP) de = 1/ 4 x 3,14 (De)2 x SG x 1000
Keterangan :
de = Loading Density Kg/m
De = Diameter Lubang tembak Inchi
SG = Spesific Gravity
b. Perhitungan Volume Hasil Peledakan dari Geometri peledakan Pada tambang
terbuka atau quary, yang umumnya menerapkan peledakan jenjang atau bench blasting,
volume batuan yang akan diledakkan tergantung pada burden, spasi, tinggi jenjang, dan
jumlah lubang. (sumber : diktat kuliah teknik peledakan, UNP)
Volume peledakan perlubang = B x S x H
Total volume peledakan = (B x S x H) x jumlah lubang
Panjang kolom isian = berat handak perlubang / loading density
B. Data dan Pengolahan Data
1) Data
Adapun data-data yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut :
(a) Pola pemboran yang dilakukan selang-seling (staggered pattern).
(b) Pada umumnya arah pemboran ang dilakukan adalah arah pemboran tegak lurus.
(c) Alat bor yang digunakan dalam proses pemboran lubang ledak yaitu alat bor dengan
merk Furukawa dengan diameter mata bor 5,5 inch dan panjang batang bor 6 meter.
2) Pengolahan Data
(a) Geometri peledakan
Data geometri peledakan pada bulan Februari 2011 di PT. Nusa Alam Lestari adalah
sebagai berikut :
Burden rata-rata = burden perhari / jumlah hari
= 4,5 m / 28
= 126 / 28
= 4,5 m
Spasi rata-rata = spasi perhari / jumlah hari
= 5,5 m / 28
= 5,5 m
Kedalaman lubang = kedalaman perhari / jumlah hari
= 5 m / 28 = 5 m
Jumlah lubang = jumlah lubang perhari / jml hari
= 1725 / 28 = 61,6 lubang = 62 lubang
Jumlah lubang dalam bulan februari diuraikan pada lampiran m
(b) Volume Peledakan V = B x S x H
= 4,5 x 5,5 x 5 = 123,75 m3 (BCM)
Sementara pada hitungan perhari terdapat 62 lubang, maka : Volume peledakan =
volume batuan x jumlah lubang
V = (B x S x H) x 62
V = 123,75 x 62
V = 7672,5 m3 (BCM)
dalam bulan Februari terdapat 28 hari, maka : = volume peledakan perhari x 28 =
7.672,5 m3 x 28 = 214.830 m3
(c) Panjang Kolom Isian PC = H - T
Keterangan :
PC = Panjang kolom isian (m)
H = Kedalaman lubang ledak (m)
T = Stemming (m)
T (stemming) yang digunakan di PT. Nusa Alam Lestari adalah sebesar 2 m (ketentuan
perusahaan) Jadi,
PC = H T = 5 m 2 m = 3 m
(d) Pemakaian Bahan Peledak Loading Density merupakan banyaknya bahan peledak
untuk setiap panjang kolom lubang ledak :
de = 1/ 4 x 3,14 (De)2 x SG x 1000
Keterangan :
de = Loading Density Kg/m
De = Diameter Lubang tembak Inchi
SG = Spesific Gravity
de = 1/ 4 x 3,14 (De)2 x SG x 1000
= 1/ 4 x 3,14 (5,5 inch)2 x 0,80 x 1000
= 1/ 4 x 3,14 (0,139 m)2 x 0,80 x 1000 = 12,13 kg/m
Berat isian ANFO untuk setiap lubang
E = de x Pc = 12,13 kg/m x 3 m = 36,39 kg
(e) Kebutuhan ANFO Untuk Setiap Lubang Pemakaian bahan Ammonium Nitrat (AN)
peledak untuk setiap lubang dapat di uraikan menggunakan rumus, yakni :
Berat AN = berat tot handak perlubang/100 X95,5
= 36,39/100 x 95,5 = 34,75 kg
Kebutuhan Fuel Oil (FO) untuk setiap lubang juga dapat diuraikan menggunakan rumus,
yakni :
Berat FO = berat tot handak perlubang/100 X 55,5
Berat FO = 36,5/100 x 55,5 = 2, 00 kg
= berat FO/BJFO
= 2,00/0,8 = 2,50 liter
Jumlah pemakaian AN untuk jumlah lubang ledak perhari
= jumlah bahan peledak perlubang x jumlah lubang ledak
= 34,75 kg x 62
= 2154, 5 kg AN
Jumlah pemakaian FO untuk jumlah lubang ledak perhari = jumlah FO perlubang x
jumlah lubang ledak
= 2,50 liter x 62 = 155 liter FO
3) Penyelesaian Masalah Berdasarkan data aktual di lapangan dengan menggunakan
burden 4,5m, spasi 5,5m dan kedalaman lubang ledak 5 kita mendapatkan volume
sebesar 123,75 m3. Maka, dari planing peledakan sebesar 300.000 BCM per bulan, kita
dapat menghitung :
= data aktual/jmlh lubang ledak = target produksi peledakan/ x
= 214.830 BCM/62 300.000/x
214.830 m3 x = 300.000 x 62
214.830 m3 x = 18.600.000
x = 18.600.000/214.830
x = 86,5 lubang
= 86 lubang/ hari
Total kebutuhan ANFO setelah terjadi penambahan jumlah lubang ledak perhari adalah
:
Ammonium Nitrat (AN) = Jumlah kebutuhan AN perlubang x jumlah lubang
AN = 34,75 kg x 86
AN = 2988 kg/perhari
Fuel Oil (FO) = jumlah FO x jumlah lubang
FO = 2,50 liter x 86
FO = 215 liter/hari
Anda mungkin juga menyukai
- Tabel Mineral-Mineral AlamDokumen5 halamanTabel Mineral-Mineral AlamElvira WeaBelum ada peringkat
- Mekanika Batuan Metode Bishop DisederhanakanDokumen6 halamanMekanika Batuan Metode Bishop DisederhanakanElvira Wea100% (1)
- Pemindahan Tanah Mekanis. BiburDokumen24 halamanPemindahan Tanah Mekanis. BiburAndi Firdaus Biboer'sBelum ada peringkat
- GampingDokumen6 halamanGampingElvira WeaBelum ada peringkat