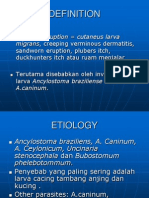Case - Jum Suwarni Stroke Iskemik
Case - Jum Suwarni Stroke Iskemik
Diunggah oleh
FebiFascinateD'meeanHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Case - Jum Suwarni Stroke Iskemik
Case - Jum Suwarni Stroke Iskemik
Diunggah oleh
FebiFascinateD'meeanHak Cipta:
Format Tersedia
1
I. Identitas
Nama : Jum Suwarni
Nomor Rekam Medik : 01308587
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 61 tahun
Agama : Islam
Alamat : Jalan Tegal Parang Utara RT/RW 12/04, Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Suku : Jawa
Status : Menikah
Masuk Rumah Sakit : 9 Juli 2014
II. Anamnesis
Anamnesis dilakukan secara autoanamnesis pada tanggal 10 Juli 2014
Keluhan Utama
Pasien tidak dapat menggerakkan lengan dan kaki sebelah kanan semenjak
2 hari sebelum masuk Rumah Sakit.
Keluhan Tambahan
o Pusing
o Mual muntah
o Kekakuan tangan
o Bicara pelo
Riwayat Penyakit Sekarang
Seorang wanita datang ke IGD RSUP Fatmawati dengan keluhan tidak
dapat menggerakkan lengan dan kaki sebelah kanan semenjak 2 hari
SMRS. Keluhan dirasakan semakin memberat dan menetap.
Keluhan ini didahului nyeri kepala yang berputar dan tidak dipengaruhi
oleh posisi dan tidak disertai gangguan pendengaran dan dirasakan kaku
pada lengan sebelah kanan, setelah pasien beristirahat dan sahur. Tiba-tiba
pasien merasa kaki kanan menjadi berat dan sulit untuk diangkat dan
digerakkan. Setelah itu pasien, berjalan pincang. Bicara pasien juga
2
menjadi tidak jelas dan dirasakan menjadi pelo. Semenjak kejadian pasien
mengaku sadar terus dan tidak pingsan. Namun, pasien mengaku ada mual
dan muntah, sebanyak 3 kali sebelum masuk Rumah Sakit dan berisi
makanan dan tidak menyemprot.
Kejang, demam, kejang, gangguan Buang Air Besar dan buang air kecil
disangkal oleh pasien
Riwayat Penyakit Dahulu
Pasien menyangkal sebelumnya pernah mengalami keluhan tidak dapat
menggerakkan anggota badan seperti ini sebelumnya. Riwayat darah tinggi
diakui oleh pasien dan tidak pernah diobati, namun pasien mengkonsusi
kaptopril tanpa anjuran/ resep dari dokter. Riwayat kencing manis
disangkal oleh pasien. Riwayat stroke disangkal oleh pasien. Pasien
menyangkal adanya kelainan jantung semenjak lahir.
Riwayat Penyakit Keluarga
Di keluarga pasien ada yang alami hal yang sama, yaitu ibu pasien. Ibu
pasien sebelum meninggal mengalami kelumpuhan pada lengan dan kaki
sebelah kanan. Pasien menyangkal adanya riwayat darah tinggi pada
keluarga pasien.
Riwayat Pengobatan
Pasien sering mengkonsumsi captopril tanpa anjuran maupun kontrol dari
dokter, untuk mengatasi darah tinggi namun tidak digunakan secara rutin.
III. Pemeriksaan Fisik
Keadaan Umum : Tampak Sakit Sedang
Kesadaran : Compos Mentis
Sikap : Berbaring
Kooperatif : Kooperatif
Kesan Gizi : Berlebih
Antopometrik : BB : 165 cm
TB : 65 kg
BMI : 23,88
Tanda Vital : Tekanan Darah : 140/90 mmHg
3
Frekuensi Nadi : 76 kali/menit
Frekuensi Respirasi : 20 kali/menit
Suhu : 36,5
0
C
Status Generalisata
Trauma stigmata : Tidak ada trauma
Pulsasi A.carotis : Teraba, kanan = kiri, reguler, equal
Perdarahan perifer : Capillary Refill Time < 2 detik
Columna Vertebralis : Letak di tengah skoliosis (-), Lordosis (-)
Kulit : Warna sawo matang, sianosis (-), ikterik (-)
Kepala : Normosefali, simetris, rambut hitam, distribusi merata, tidak
mudah dicabut, tidak ada alopesia, tidak ada benjolan, nyeri
tekan (-).
Mata : Ptosis -/-, Lagophthalmus -/-, Konjungtiva anemis (-), Sklera
ikterik (-), pupil bulat isokor dengan diameter 3 mm/3mm
Hidung : Deviasi septum -/-, perdarahan -/-, sekret -/-
Telinga : Normotia -/-, perdarahan -/-, sekret -/-, Battles sign -/-
Mulut : Bibir edema (-), lidah kotor (-), perdarahan (-). Gigi geligi
tidak lengkap (-)
Leher : Bentuk simetris, trakea lurus di tengah, tidak teraba
pembesaran KGB dan tiroid.
Thorax :
Paru-paru
Inspeksi : bentuk dada barrel chest (-), bentuk tulang dada datar, sela iga
normal, retraksi sela iga (-/-), gerakan dinding dada saat statis dan dinamis
simetris
Palpasi : vocal fremitus simetris, pergerakan dinding dada saat bernapas
simetris
Perkusi : sonor di kedua lapang paru
Auskultasi: suara napas vesikuler, wheezing (-/-), ronchi (-/-)
Jantung
4
Inspeksi : ictus cordis tidak terlihat
Palpasi : ictus cordis teraba di ICS V 1 cm linea midclavicularis sinistra
Perkusi : batas jantung kiri ICS V 1 cm medial linea midclavicularis sinistra,
batas jantung atas di ICS III linea parasternalis sinistra, batas jantung kanan di
ICS III-V linea sternalis dekstra
Auskultasi: suara jantung I dan II, reguler, murmur (-), gallop (-)
Abdomen
Inspeksi : perut tampak datar, gerakan abdomen saat pernapasan (+), simetris
Auskultasi: bising usus (+)
Palpasi : supel, nyeri tekan (-), defans muscular (-), massa (-), hepar tidak
teraba, lien tidak teraba, tidak teraba massa pemeriksaan Ballotement (-/-)
Perkusi : timpani pada seluruh kuadran
Ekstremitas :
Ekstremitas Superior
Inspeksi (Look)
Dekstra Inspeksi
(Look)
Sinistra
Normal dan
proporsiona
l
Bentuk
dan
ukuran
Normal dan
proporsiona
l
Hitam dan
merata
Rambut
kulit
Hitam dan
merata
(-) Ulserasi (-)
(-) Peradanga
n
(-)
5
(-) Oedema (-)
(-) Palmar
eritema
(-)
Normal Tonus otot Normal
Eutrofi Trofi otot Eutrofi
Palpasi (Feel)
Dekstra Palpasi
(Feel)
Sinistra
Hangat
dan
lembab
Suhu dan
kelembaban
Hangat
dan
lembab
(-) Massa (-)
(-) Nyeri tekan (-)
Baik Tonus otot Baik
Eutrofi Trofi otot Eutrofi
(-) Oedema (-)
Ekstremitas Inferior
Inspeksi (Look)
Dextra Inspeksi (Look) Sinistra
Normal dan
proporsional
Bentuk dan
ukuran
Normal dan
proporsional
Hiperemis (-
), pucat (-)
Warna kulit Hiperemis (-
), pucat (-)
6
Hitam dan
merata
Rambut kulit Hitam dan
merata
(-) Ulserasi (-)
(-) Peradangan (-)
(-) Oedema (-)
Normal Tonus otot Normal
Eutrofi Trofi otot Eutrofi
Palpasi (feel)
Dextra Palpasi (Feel) Sinistra
Hangat dan
lembab
Suhu dan
kelembaban
Hangat dan
lembab
(-) Massa (-)
(-) Nyeri tekan (-)
Normal Tonus otot Normal
Eutrofi Trofi otot Eutrofi
(-) Oedema (-)
A. Status Neurologis
PEMERIKSAAN NEUROLOGIS
A. Rangsang Selaput Otak
Kaku kuduk : negatif
Laseque : >70 / >70
Kernig : >135 / >135
Brudzinski I : (-/-)
7
Brudzinski II : (-/-)
B. Peningkatan Tekanan Intrakranial
Muntah proyektil : disangkal oleh pasien
Papil edema : tidak dilakukan pemeriksaan
Sakit kepala hebat: disangkal oleh pasien
C. Saraf-saraf cranialis
N. I (olfaktorius) : baik
N. II (optikus)
Acies visus : baik/baik
Visus campus : baik/baik
Warna : baik/baik
Funduskopi : baik/baik
N. III, IV, VI (okulomotorius, trochlearis, abducens)
Kedudukan bola mata : orthoforia +/+
Pergerakan bola mata
Nasal : baik/baik
Temporal : baik/baik
Superior : baik/baik
Inferior : baik/baik
Nasal atas : baik/baik
Nasal bawah : baik/baik
Temporal atas : baik/baik
Temporal bawah : baik/baik
8
Exopthalmus : (-/-)
Strabismus : (-/-)
Nistagmus : (-/-)
Pupil : isokor
Bentuk dan ukuran : bulat 3 mm /
bulat 3 mm
Refleks cahaya langsung : (+/+)
Refleks cahaya tidak langsung: (+/+)
Akomodasi : baik
Konvergensi : baik
N. V (trigeminus)
Cabang motorik
Membuka mulut : baik
Mengunyah : baik
Menggigit : baik
Cabang sensorik
Refleks kornea : (+/+)
Opthalmikus : baik
Maksilaris : baik
Mandibularis : baik
N. VII (fasialis)
Motorik orbitofrontal : baik / baik
Motorik orbicularis okuli : baik / baik
9
Motorik orbicularis oris : baik / melemah, didapatkan
plica nasolabialis sinistra lebih datar.
Pengecapan lidah : baik
N. VIII (vestibulocochlearis)
Vestibular
Vertigo : -
Nistagmus : -
Cochlear
Rhinne : baik
Weber : baik
Swabach : baik
Tes bisik : baik
N.IX (glossopharyngeus)
Motorik menelan : baik
Sensorik (1/3 posterior lidah) : baik
N. X (vagus)
Motorik : Baik
Sensorik : Baik
N.XI (accesorius)
Mengangkat bahu : baik
Menoleh : baik
N.XII (hypoglossus)
Pergerakan lidah : di dalam rongga mulut lidah tertarik ke
10
arah kanan
Atrofi : (-)
Fasikulasi: (-)
Tremor: (-)
D. Sistem Motorik
Ekstremitas atas proksimal distal : 5554 | 5555
Ekstremitas bawah proksimal distal : 5533 | 5555
D. Sistem sensorik
propioseptif : baik
eksteroseptif : baik
E. Trofik : eutrofik (+/+)
F. Tonus : normotonus (+/+)
G. Gerakan involunter
Tremor : (-/-)
Chorea : (-/-)
Athetose : (-/-)
Miokloni : (-/-)
Tics : (-/-)
H. Fungsi Otonom
Miksi : baik
Defekasi : baik
I. Refleks-refleks Fisiologis
Biseps : (+3/+2)
Triseps : (+3/+2)
Patela : (+3/+2)
11
Achiles : (+3/+2)
J. Refleks Patologis
Hoffman Tromer : (-/-)
Babinsky : (-/-)
Chaddok : (-/-)
Gordon : (-/-)
Schaefer : (-/-)
Klonus patella : (-/-)
Klonus tumit : (-/-)
K. Koordinasi, Gait dan Keseimbangan
Cara berjalan : Kaki kanan diseret dan agak diangkat
Tes Romberg : tidak valid dinilai
Disdiadokinesia : baik
Jari ke hidung : baik
Tumit ke lutut : tidak valid dinilai
Rebound fenomena : (-)
L. Fungsi Luhur
Astereognosia : (-)
Apraxia : (-)
Afasia : (-)
M. Keadaan psikis
Intelegensia : baik
Tanda regresi : (-)
Demensia : (-)
12
IV. Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan Laboratorium
HEMATOLOGI Hasil Satuan Nilai
rujukan
Hemoglobin 12,3 g/dl 12-16
Hematokrit 37 % 35-45
Leukosit 5.3 Ribu/uL 5-10
Trombosit 252 Ribu/uL 150-450
Eritrosit 4.12 Juta/uL 4-6
Indeks Eritrosit
MCV 89,3 Fl 82-92
MCH 29.9 Pg 27-37
MCHC 33.5 % 32-37
RDW 14.9 % 11.5-14.5
Kimia Klinik
Faal Hepar
SGOT 30 U/l 0-34
SGPT 34 U/l 0-40
Fungsi Ginjal
Ureum 36 Mg/dl 20-40
Creatinin 0,6 Mg/dl 0.6-1.5
Glukosa darah 108 Mg/dl 70-140
13
sewaktu
Elektrolit Darah
Na 144 Mmol/L 135-145
K 2.71 Mmol/L 3.5-5.0
Cl 110 Mmol/L 94-108
Pemeriksaan Foto Roentgen
Foto Thorax AP
Posisi asimetris
Trakea relatif di tengahMediastinum superior sisi kanan melebar (dd/ vaskular)
Jantung kanan sedikit membesar
Aorta kalsifikasi
Hilus kedua paru tidak menebal
Corakan bronchovaskular normal
Tidak tampak infiltrat di kedua lapangan paru
Diafragma dan sinus kostofrenikus normal
Tulang-tulang kesan intak
14
Kesan: Cardiomegali dengan aorta kalsifikasi, paru dalam batas normal
Pemeriksaan CT-Scan
Pada pemeriksaaan CT-Scan kepala potongan aksian dengan tebal 3 mm di basis
dan 10 mm di serebral, tanpa pemberian kontras
Tampak lesi hipodens berbatas tidak tegas di lobus frontoparietal kiri dan
parietalis kanan serta curiga lesi hipodens di ganglia basall kiri (HU sedikit lebih
rendah dibanding kontralateral)
15
Sulci dan gyri baik
Sistem ventrikel normal dan simetris
Fissura sylvii dan sistena ambiens tidak menyempit
Tak tampak midline shift
Serebellum dan pons baik
Kalsifikasi fisiologis pleksus choroidalis ventrikel lateralis cornu posterior
bilateral
Sinus paranasalis baik
Tulang-tulang kepala baik
Kesan : Infark Cerebri di subkortikal lobus temporalis dan parietalis kanan.
Suspek infark cerebri di basal ganglion kiri.
V. Resume
Pasien dengan keluhan tidak dapat menggerakkan lengan dan kaki sebelah kanan
semenjak 2 hari SMRS. Sebelumnya, keluhan didahului dengan sakit kepala berputar
yang tidak berat awalnya yang sulit digerakkan tangan kanan, kemudian kaki sebelah
kanan tidak dapat digerakkan dan jalan menjadi pincang. Selain itu, bicara menjadi tidak
jelas dan menjadi pelo. Pasien sadar terus, tidak pingsan. Mual (+) muntah (+) 3 kali
sebelum masuk RS, isi makanan dan tidak menyemprot. Pasien memiliki riwayat darah
tinggi yang tidak terkontrol, namun pasien sering konsumsi kaptopril tanpa kontrol ke
dokter. Ibu pasien meninggal karena stroke.
Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan kelainan berupa pasien yang tampak sakit
sedang dan obesitas menurut hasil BMI. Tidak didapatkan kelainan dari status
generalisata. Dari status neurologis didapatkan penurunan kekuatan otot pada lengan dan
kaki dextra dan hiperrefleksia dextra. Dari nervus cranialis didapatkan parese N. VII
sentral dekstra dan N. XII sentral dekstra.
Dari pemeriksaan penunjang kelainan pada laboratprium darah yaitu hipokalemi.
Pemeriksaan roentgen thorax didapatkan thorax didapatkan kardiomegali dengan aorta
kalsifikasi, paru dalam batas normal. Dari pemeriksaan CT-scan didapatkan kesan infark
cerebri di subkortikal lobus temporalis dan parietalis kanan. Suspek infark cerebri di basal
ganglion kiri.
16
VI. Diagnosis
a. Diagnosis Topis : Subkorteks
b. Diagnosis Klinis : Hemiparesis dextra
c. Diagnosis Etiologi : Infark serebri
d. Diagnosis Kerja : Stroke Iskemik hari ke-2 dan Hipokalemia
VII. Penatalaksanaan
o Non-medika mentosa
Elevasi kepala 30
O
C
Stabilisasi fungsi kardiologis dengan ABC
O
2
dengan nasal kanul 2L/jam
o Medika Mentosa
Neulin 2 x 1000
Fepiram 1x 3 gr
Pletacil 1 x 50 mg
NaCl 0,9% + KCl 25 meq/ 12 jam
VIII. Prognosis
Ad vitam : Bonam
Ad functionam : Bonam
Ad sanationam : Dubia Ad Bonam
17
BAB I
PENDAHULUAN
Stroke menjadi penyebab kematian tertinggi di wilayah perkotaan. Jumlahnya mencapai 15.9
persen dari proporsi penyebab kematian di Indonesia (Riser kesehatan Dasar/ Riskerdas tahun 2007).
Di Indonesia menurut survey kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 1995, stroke merupakan salah
satu penyebab kematian dan kecacatan yang utama yang harus ditangani segera, tepat dan cermat.
Penderita stroke saat ini menjadi penghuni terbanyak di bangsal atau ruangan pada hampir
semua pelayanan rawat inap penderita penyakit saraf. Karena, selain menimbulkan beban ekonomi
bagi penderita dan keluarganya, stroke juga menjadi beban bagi pemerintah dan perusahaan asuransi
kesehatan, berbagai fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini, stroke masih merupakan masalah
utama dibidang neurologi maupun kesehatan pada umumnya. Untuk mengatasi masalah penting ini
diperlukan strategi penanggulangan stroke yang mencakup aspek preventif, terapi rehabilitasi dan
promotif.
18
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
STROKE
A. DEFINISI
Stroke adalah sindrom klinik yang dikarakterisasikan dengan gejala klinis yang
berkembang dengan cepat dan atau tanda fokal, terkadang global hilangnya fungsi otak,
dengan gejala yang berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian, dengan
penyebab vaskular (Hatano, 1976). Definisi ini termasuk stroke yang disebabkan oleh infark,
primary intracerebral hemorrhage (PICH), perdarahan intraventrikular, dan lain sebagainya.
B. EPIDEMIOLOGI
Di Eropa, stroke adalah penyebab kematian nomor tiga di negara-negara industri di
Eropa. Insidens global stroke diperkirakan akan semakin meningkat sejak populasi manula
berusia lebih dari 65 tahun meningkat dari 390 juta jiwa menjadi 800 juta jiwa yang
diperkirakan pada tahun 2025. Stroke iskemik adalah tipe yang paling sering ditemukan, kira-
kira 85% dari seluruh kasus stroke. Sedangkan stroke hemoragik mencakup 15% dari seluruh
kasus stroke. Di USA, sebanyak 705.000 kasus stroke terjadi setiap tahun, termasuk kasus
baru dan kasus rekuren. Dari semua kasus tersebut, hanya 80.000 kasus adalah stroke
hemoragik.
C. ETIOLOGI
Lesi vaskular di susunan saraf bisa berarti lesi di otak dan batang otak di satu pihak
dan lesi di medula spinalis di lain pihak. Penyakit-penyakit dengan lesi vaskular di otak
dikenal dengan lesi vaskular di otak dikenal sebagai penyakit serebrovaskular atau disingkat
CVD (Cerebro Vascular Disease). Penggunaan istilah CVD mencerminkan kesediaan untuk
menyelami penyakit yang mendasari stroke. Stroke atau manifestasi CVD mempunyai
etiologi dan pembahasan patogenesis yang multikompleks.
19
Lesi-lesi vaskular regional yang terjadi di otal sebagian besar disebabkan oleh proses
oklusi pada lumen arteri serebral. Sebagian lainnya disebabkan oleh pecahnya pembuluh
darah. Penyakit vaskular utama yang menimbulkan penyumbatan ialah aterosklerosis dan
arteriosklerosis. Penyakit-penyakit vaskular oklusif lainnya ialah endartritis reumatik dan
sifilik, periatritis nodusa dan lupus sistematous diseminata.
Faktor resiko terjadinya stroke meliputi faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan
yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya seperti,
1. Faktor resiko yang dapat dikendalikan
a. Hipertensi
b. Profil lipid darah
c. Obesitas
d. Diabetes Mellitus
2. Faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan
a. Jenis Kelamin
b. Umur
c. Ras
d. Kelainan kongenital, seperti kelainan katup, aneurisma, arteri-vena
malformasi
D. KLASIFIKASI
Stroke sebagai diagnosis klinis untuk gambaran manifestasi lesi vaskular serebral,
dapat dibagi dalam:
1. Berdasarkan PA/Etiologi
a. Stroke Iskemik
Trombosis Serebri
Emboli Serebri
b. Stroke Hemoragik
ICH
SAH
2. Berdasarkan stadium/waktu
Transient Ischemic Attack
20
Reversible Iskemik Neuro Deficit
Stroke inevolution
Complete Stroke
3. Berdasarkan sistem pembuluh darah
Sistem Karotis/anterior
Sistem Vertebrobasiler/posterior
E. PATOFISIOLOGI
Gangguan pasokan aliran darah otak dapat terjadi di mana saja di dalam artei-arteri yang
membentuk sirkulus Wilillisi: arteri karotis interna dan sistem vertebrobasilar atau semua
cabang-cabangnya. Secara umum, apabila aliran darah ke jaringan otak terputus selama 15
sampai 20 menit, akan terjadi infark atau kematian jaringan. Oklusi di suatu arteri tidak selalu
menyebabkan infark di daerah otak yang diperdarahi oleh arteri tersebut. Alasannya adalah
bahwa mungkin terdapat sirkulasi kolateral yang memadai ke daerah tersebut. Proses
patologik yang mendasari mungkin salah satu dari berbagai proses yang terjadi dalam
pembuluh darah yang memperdarahi otak. Patologinya dapat berupa (1) keadaan penyakit
pada pembuluh itu sendiri, seperti pada aterosklerosis dan trombosis, robeknya dinding
pembuluh, atau peradangan; (2) berkurangnya perfusi akibat gangguan status aliran darah,
misalnya syok atau hiperviskositas darah; (3) gangguan aliran darah akibat bekuan atau
embolus infeksi yang berasal dari jantung atau pembuluh ekstrakranium; atau (4) ruptur
vaskular di dalam jaringan otak atau ruang subaraknoid.
Penghentian total aliran darah ke otak akan menyebabkan hilangnya kesadaran dalam waktu
15-20 detik dan kerusakan otak yang irreversibel terjadi setelah 7-10 menit. Penyumbatan
pada satu arteri menyebabkan gangguan di area otak yang terbatas (stroke). Mekanisme
dasasr kerusakan ini adalah defisiensi energi yang disebabkan oleh iskemia (misal:
arterosklerosis, emboli). Perdarahan akibat trauma, aneurisma vaskular dan hipertensi juga
menyebabkan iskemia dengan menekan pembuluh darah di sekitarnya.
Kelangsungan hidup sel tergantung dari kemampuan mempertahankan volume sel dan
lingkungan intrasel. Kemampuan untuk mempertahankan volume sel tergantung dari
keseimbangan osmotiknya. Untuk menyeimbangkan konsentrasi protein, asam amino, dan
substrat organik lainnya yang tinggi di intrasel, sel menurunkan konsentrasi ionnya di sitosol.
Hal ini dilakukan oleh Na
+
/K
+
-ATPase yang memompa Na+ ke luar sel untuk ditukar dengan
21
K+. Normalnya membran sel hanya sedikit permeabel untuk Na+ tetapi sangat permeabel
terhadap K+ sehingga K+ akan kembali berdifusi ke luar. Aliran K+ ini menghasilkan
potensial negatif di bagian dalam sehingga mendorong Cl- ke luar dari sel.
8
Homeostasis Na+ di intrasel dapat terganggu bila aktivitas Na
+
/K
+
-ATPase terhambat
karena kekurangan ATP, akibatnya, K+ intrasel menurun dan K+ ekstrasel sebaliknya
meningkat, sera membran sel menjadi depolarisasi. Cl- akan masuk ke dalam sel dan sel
membengkak. Keadaan ini juga terjadi bila suplai energi berkuran atau bila masukan Na+
melebihi kapasitas transpor maksimal Na
+
/K
+
-ATPase.
Peningkatan
konsentrasi Na+
intrasel tidak hanya
menyebabkan
pembengkakan sel,
tetapi juga
meningkatkan
konsentrasi Ca+2
yang dapat masuk ke
dalam mitokondria
dan menyebabkan kekurangan ATP melalui penghambatan proses respirasi mitokondria.
Jika terdapat kekurangan O2 metabolisme energi berubah menjadi glikolisis anaerob.
Pembentukan asam laktat, yang berdisosiasi menjadi laktat dan H+, menimbulkan asidosis.
Keadaan ini mengganggu fungsi enzim intrasel sehingga menghambat proses glikolisis yang
merupakan sumber ATP terakhir menjadi terhenti.
Bila kekurangan energi semakin berlanjut, sel cenderung terpajan dengan kerusakan
oksidatif karena mekanisme perlindungan sel untuk melawan oksidan sangat tergantung pada
ketersediaan ATP. Oleh karena itu, terjadi resiko kerusakan membran sel dan pelepasan
makromolekul intrasel ke ruang intrasel. Karena sistem imun biasanya tidak terpajan dengan
makromolekul intrasel, toleransi imun terhadap makromolekul tidak bisa terbentuk.
Akibatnya sistem imun teraktifkan dan timbul proses peradangan yang semakin
menyebabkan kerusakan sel yaitu merusak sel di tepi area iskemik (penumbra).
Aterosklerosis atau trombosis biasanya dikaitkan dengan kerusakan lokal
pembuluh darah akibat aterosklerosis. Proses aterosklerosis ditandai dengan adanya plak
berlemak pada lapisan intima arteria besar. Bagian intima arteri serebri menjadi tipis dan
berserabut, sedangkan sel-sel ototnya menghilang. Lamina elastika interna robek dan
22
berjumbai, sehingga lumen pembuluh darah sebagian terisi oleh materi sklerotik. Plak
cenderung terbentuk pada daerah percabangan ataupun tempat-tempat yang melengkung.
Trombosit yang menghasilkan enzim mulai melakukan proses koagulasi dan menempel pada
permukaan dinding pembuluh darah yang kasar. Sumbat fibrinotrombosit dapat terlepas dan
membentuk emboli atau dapat tetap tinggal di tempat dan menutup arteri secara sempurna.
Emboli kebanyakan berasal dari suatu thrombus dalam jantung, dengan kata lain
hal merupakan perwujudan dari masalah jantung. Meskipun lebih jarang terjadi embolus juga
mungkin berasal dari plak ateromatosa sinus karotis atau arteri karotis interna. temapt yang
paling sering terserang emboli serebri adalah arteri serebri media, terutama bagian atas.
Perdarahan intraserebral sebagian besar terjadi akibat hipertensi dimana tekanan
darah diastoliknya melebihi 100 mmHg. Hipertensi kronik dapat menyebabkan pecah/ruptur
arteri serebri. Ekstravasasi darah terjadi di daerah otak dan/atau subarakhnoid, sehingga
jaringan yang terletak di dekatnya akan tergeser dan tertekan. Daerah distal dari tempat
dinding arteri pecah tidak lagi kebagian darah sehingga daerah tersebut menjadi iskemik dan
kemudian menjadi infark yang tersiram darah ekstravasal hasil perdarahan. Daerah infark itu
tidak berfungsi lagi sehingga menimbulkan deficit neurologik, yang biasanya menimbulkan
hemiparalisis. Dan darah ekstravasal yang tertimbun intraserebral merupakan hematom yang
cepat menimbulkan kompresi terhadap seluruh isi tengkorak berikut bagian rostral batang
otak. Keadaan demikian menimbulkan koma dengan tanda-tanda neurologik yang sesuai
dengan kompresi akut terhadap batang otak secara rostrokaudal yang terdiri dari gangguan
pupil, pernapasan, tekanan darah sistemik dan nadi. Apa yang dilukis diatas adalah gambaran
hemoragia intraserebral yang di dalam klinik dikenal sebagai apopleksia serebri atau
hemorrhagic stroke.
9
Arteri yang sering pecah adalah arteria lentikulostriata di wilayah kapsula interna.
Dinding arteri yang pecah selalu menunjukkan tanda-tanda bahwa disitu terdapat aneurisme
kecil-keci yang dikenal sebagai aneurisme Charcot Bouchard. Aneurisma tersebut timbul
pada orang-orang dengan hipertensi kronik, sebagai hasil proses degeneratif pada otot dan
unsure elastic dari dinding arteri. Karena perubahan degeneratif itu dan ditambah dengan
beban tekanan darah tinggi, maka timbullah beberapa pengembungan kecil setempat yang
dinamakan aneurismata Charcot Bouchard. Karena sebab-sebab yang belum jelas,
aneurismata tersebut berkembang terutama pada rami perforantes arteria serebri media yaitu
arteria lentikolustriata. Pada lonjakan tekanan darah sistemik seperti sewaktu orang marah,
mengeluarkan tenaga banyak dan sebagainya, aneurima kecil itu bisa pecah. Pada saat itu
juga, orangnya jatuh pingsan, nafas mendengkur dalam sekali dan memperlihatkan tanda-
23
tanda hemiplegia. Oleh karena stress yang menjadi factor presipitasi, maka stroke
hemorrhagic ini juga dikenal sebagai stress stroke.
Pada orang-orang muda dapat juga terjadi perdarahan akibat pecahnya aneurisme
ekstraserebral. Aneurisme tersebut biasanya congenital dan 90% terletak di bagian depan
sirkulus Willisi. Tiga tempat yang paling sering beraneurisme adalah pangkal arteria serebri
anterior, pangkal arteria komunikans anterior dan tempat percabangan arteria serebri media di
bagian depan dari sulkus lateralis serebri. Aneurisme yang terletak di system vertebrobasiler
paling sering dijumpai pada pangkal arteria serebeli posterior inferior, dan pada percabangan
arteria basilaris terdepan, yang merupakan pangkal arteria serebri posterior.
Fakta bahwa hampir selalu aneurisme terletak di daerah percabangan arteri
menyokong anggapan bahwa aneurisme itu suatu manifestasi akibat gangguan perkembangan
embrional, sehingga dinamakan juga aneurisme sakular (berbentuk seperti saku) congenital.
Aneurisme berkembang dari dinding arteri yang mempunyai kelemahan pada tunika
medianya. Tempat ini merupakan tempat dengan daya ketahanan yang lemah (lokus minoris
resistensiae), yang karena beban tekanan darah tinggi dapat menggembung, sehingga dengan
demikian terbentuklah suatu aneurisma.
Aneurisme juga dapat berkembang akibat trauma, yang biasanya langsung
bersambung dengan vena, sehingga membentuk shunt arteriovenosus.
Apabila oleh lonjakan tekanan darah atau karena lonjakan tekanan intraandominal,
aneurisma ekstraserebral itu pecah, maka terjadilah perdarahan yang menimbulkan gambaran
penyakit yang menyerupai perdarahan intraserebral akibat pecahnya aneurisma Charcor
Bouchard. Pada umumnya factor presipitasi tidak jelas. Maka perdarahan akibat pecahnya
aneurisme ekstraserebral yang berimplikasi juga bahwa aneurisme itu terletak
subarakhnoidal, dinamakan hemoragia subduralis spontanea atau hemoragia subdural primer.
Gejala ditentukan oleh tempat perfusi yang terganggu, yakni daerah yang disuplai
oleh pembuluh darah tersebut.
1. Penyumbatan pada a. Serebri media sering terjadi menyebabkan
- Kelemahan otot dan spastisitas kontralateral
- Defisit sensorik (hemianestesia) akibat kerusakan girus lateral presentralis dan post
sentralis
- Deviasi okular (deviation conjugee) akibat kerusakan area motorik penglihatan
- Hemianopsia (kebutaan)
- Gangguan bicara motok dan sensorik
24
- Gangguan persepsi spasial
- Apraksia
- Hemineglect (lobus parietalis)
2. Penyumbatan pada a. Serebri anterior menyebabkan:
- Hemiparesis dan defisit sensorik kontralateral akibat kehilangan girus presentralis
dan postsentralis bagian medial
- Kesulitan berbicara akibat kerusakan area motorik
- Apraksia pada lengan kiri jika korpus kalosum anterior dan hubungan dari hemisfer
dominan ke korteks motorik kanan terganggu.
- Apatis akibat kerusakan dari sistem limbik
3. Penyumbatan pada a. Serebri posterior menyebabkan:
- Hemianopsia kontralateral parsial
- Kebutaan jika penyumbatan terjadi secara bilateral
- Kehilangan memori akibat mengenai lobus temporalis bagian bawah
25
4. Penyumbatan pada a. Karotis atau basilaris akan menyebabkan defisit di daerah yang
disuplai oleh a. Serebri media dan anterior
5. Penyumbatan pada a. karotid anterior menyebabkan ganglia basalis (hipokinesia),
kapsula interna (hemiparesis) dan traktus optikus (hemianopsia) akan terkena
6. Penyumbatan pada a. komunikans posterior di talamus akan menyebabkan defisit
sensorik.
7. Penyumbatan total a.basilaris menyebabkan
- Paralisi semua ekstremitas (tetraplegia) dan otot-otot mata
- Koma
8. Penyumbatan pada cabang a.basilaris dapat menyebkan infark pada serebelum,
mesensephalon, pons dan medula oblongata. Efek yang ditimbulkan tergantung dari
lokasi kerusakan
- Pusing, nistagmus, hemiataksia akibat kerusakan serebelum dan jaras aferen nya,
saraf vestibular
- Penyakit Parkinson akibat kerusakan subtansia nigra
- Hemiplegua kontralateral dan tetraplegia akibat kerusakan traktus piramidal
- Hilangnya sensasi nyeri dan suhu (hipestesia atau anastesia) di bagian wajah
ipsilateral dan ekstremitas kontralateral akibat kerusakan saraf trigeminus (V) dan
traktus spinotalamikus
- Hipakusis (hipestesia auditorik) akibat kerusakan saraf koklearis
- Ageusis akibat kerusakan saraf traktus salivarius
- Singultus akibat kerusakan formatio retikularis
- Ptosis, miosis dan anhidrosis fasial ipsilateral (sindrom Horner) akibat kerusakan
saraf simpatis
- Paralisis palatum molle dan takikardia akibat kerusakan nervus vagus (X)
- Paralisis otot lidah akibat kerusakan saraf hypoglosus (XII)
- Strabismus akibat kerusakan saraf okulomotorik (III), saraf abdusens (VI)
F. MANIFESTASI KLINIS
Karena lesi vaskular regional di otak timbulah hemiparalisis atau hemiparesis yang
kontralateral terhadap sisi lesi. Jika lesi vaskular menduduki daerah batang otak sesisi,
maka timbullah gambaran penyakit hemiparesis atau hemihipestesia alternans, yang
26
mana berarti bahwa hemiparesis atau hemihipestesia bersifat kontralateral. Lagi pula
saraf-saraf otak yang ikut terkena menunjukkan ciri khas itu juga. Sindrom
hemiparesis kontralateral akibat lesi regional di otak dikenal segabai stroke,
sedangkan sindrom hemiparesis/hemihipestesia alternans pada mana saraf-daraf otak
terlibat dikenal sebagai sindrom batang otak
G. PEMERIKSAAN PENUNJANG
Computerized tomography (CT scan): untuk membantu menentukan penyebab
seorang terduga stroke, suatu pemeriksaan sinar x khusus yang disebut CT scan otak sering
dilakukan. Suatu CT scan digunakan untuk mencari perdarahan atau massa di dalam otak,
situasi yang sangat berbeda dengan stroke yang memerlukan penanganan yang berbeda pula.
CT Scan berguna untuk menentukan:
Jenis patologi
Lokasi lesi
Ukuran lesi
Menyingkirkan lesi non vaskuler
MRI scan: Magnetic resonance imaging (MRI) menggunakan gelombang magnetik
untuk membuat gambaran otak. Gambar yang dihasilkan MRI jauh lebih detail jika
dibandingkan dengan CT scan, tetapi ini bukanlah pemeriksaan garis depan untuk stroke. jika
CT scan dapat selesai dalam beberapa menit, MRI perlu waktu lebih dari satu jam. MRI dapat
dilakukan kemudian selama perawatan pasien jika detail yang lebih baik diperlukan untuk
pembuatan keputusan medis lebih lanjut. Orang dengan peralatan medis tertentu (seperti,
pacemaker) atau metal lain di dalam tubuhnya, tidak dapat dijadikan subyek pada daerah
magneti kuat suatu MRI.
Metode lain teknologi MRI: suatu MRI scan dapat juga digunakan untuk secara
spesifik melihat pembuluh darah secara non invasif (tanpa menggunakan pipa atau injeksi),
suatu prosedur yang disebut MRA (magnetic resonance angiogram). Metode MRI lain
disebut dengan diffusion weighted imaging (DWI) ditawarkan di beberapa pusat kesehatan.
Teknik ini dapat mendeteksi area abnormal beberapa menit setelah aliran darah ke bagian
otak yang berhenti, dimana MRI konvensional tidak dapat mendeteksi stroke sampai lebih
dari 6 jam dari saat terjadinya stroke, dan CT scan kadang-kadang tidak dapat mendeteksi
27
sampai 12-24 jam. Sekali lagi, ini bukanlah test garis depan untuk mengevaluasi pasien
stroke.
Computerized tomography dengan angiography: menggunakan zat warna yang
disuntikkan ke dalam vena di lengan, gambaran pembuluh darah di otak dapat memberikan
informasi tentang aneurisma atau arteriovenous malformation. Seperti abnormalitas aliran
darah otak lainnya dapat dievaluasi dengan peningkatan teknologi canggih, CT angiography
menggeser angiogram konvensional.
Conventional angiogram: suatu angiogram adalah tes lain yang kadang-kadang
digunakan untuk melihat pembuluh darah. Suatu pipa kateter panjang dimasukkan ke dalam
arteri (biasanya di area selangkangan) dan zat warna diinjeksikan sementara foto sinar-x
secara bersamaan diambil. Meskipun angiogram memberikan gambaran anatomi pembuluh
darah yang paling detail, tetapi ini juga merupakan prosedur yang invasif dan digunakan
hanya jika benar-benar diperlukan. Misalnya, angiogram dilakukan setelah perdarahan jika
sumber perdarahan perlu diketahui dengan pasti. Prosedur ini juga kadang-kadang dilakukan
untuk evaluasi yang akurat kondisi arteri carotis ketika pembedahan untuk membuka
sumbatan pembuluh darah dipertimbangkan untuk dilakukan.
Carotid Doppler ultrasound: adalah suatu metode non-invasif (tanpa injeksi atau
penempatan pipa) yang menggunakan gelombang suara untuk menampakkan penyempitan
dan penurunan aliran darah pada arteri carotis (arteri utama di leher yang mensuplai darah ke
otak)
Tes jantung: tes tertentu untuk mengevaluasi fungsi jantung sering dilakukan pada
pasien stroke untuk mencari sumber emboli. Echocardiogram adalah tes dengan gelombang
suara yang dilakukan dengan menempatkan peralatan microphone pada dada atau turun
melalui esophagus (transesophageal achocardiogram) untuk melihat bilik jantung. Monitor
Holter sama dengan electrocardiogram (EKG), tetapi elektrodanya tetap menempel pada
dada selama 24 jam atau lebih lama untuk mengidentifikasi irama jantung yang abnormal.
Tes darah: tes darah seperti sedimentation rate dan C-reactive protein yang dilakukan
untuk mencari tanda peradangan yang dapat memberi petunjuk adanya arteri yang mengalami
peradangan. Protein darah tertentu yang dapat meningkatkan peluang terjadinya stroke karena
pengentalan darah juga diukur. Tes ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab stroke
yang dapat diterapi atau untuk membantu mencegah perlukaan lebih lanjut. Tes darah
screening mencari infeksi potensial, anemia, fungsi ginjal dan abnormalitas elektrolit
mungkin juga perlu dipertimbangkan.
28
Tabel a. Perbedaan jenis stroke dengan menggunakan alat bantu.
Tabel b. Gambaran CT-Scan Stroke Infark dan Stroke Hemoragik
Tabel c. Karakteristik MRI pada stroke hemoragik dan stroke infark
29
H. DASAR DIAGNOSIS
1. Siriraj Score
Catatan : 1. SSS> 1 = Stroke hemoragik
2. SSS < -1 = Stroke non hemoragik
Diantaranya : CT-scan
2. Gadjah Mada Score
30
3. Djonaedi score
31
I. PENATALAKSANAAN
Pengobatan yang cepat dan tepat diharapkan dapat menekan mortalitas dan mengurangi
kecacatan. Tujuan utama pengobatan adalah untuk memperbaiki aliran darah ke otak secepat
mungkin dan melindungi neuron dengan memotong kaskade iskemik. Pengelolaan pasien
stroke akut pada dasarnya dapat di bagi dalam :
1. Pengelolaan umum, pedoman 5 B
- Breathing
- Blood
32
- Brain
- Bladder
- Bowel
2. Pengelolaan berdasarkan penyebabnya
Stroke iskemik
Memperbaiki aliran darah ke otak (reperfusi)
Prevensi terjadinya trombosis (antikoagualsi)
Proteksi neuronal/sitoproteksi
Stroke Hemoragik
Pengelolaan konservatif
Perdarahan intra serebral
Perdarahan Sub Arachnoid
Pengelolaan operatif
Pengelolaan umum, pedoman 5 B
a. Breathing : Jalan nafas harus terbuka lega, hisap lendir dan slem untuk mencegah
kekurang oksigen dengan segala akibat buruknya. Dijaga agar oksigenasi dan
ventilasi baik, agar tidak terjadi aspirasi (gigi palsu dibuka).Intubasi pada pasien
dengan GCS < 8. Pada kira-kira 10% penderita pneumonia (radang paru) merupakan
merupakan penyebab kematian utama pada minggu ke 2 4 setelah serangan
otak.Penderita sebaiknya berbaring dalam posisi miring kiri-kanan bergantian setiap 2
jam. Dan bila ada radang atau asma cepat diatasi.
b. Blood : Tekanan darah pada tahap awal tidak boleh segera diturunkan, karena
dapat memperburuk keadaan, kecuali pada tekanan darah sistolik > 220 mmHg dan
atau diastolik > 120 mmHg (stroke iskemik), sistolik > 180 mmHg dan atau diastolik
> 100 mmHg (stroke hemoragik). Penurunan tekanan darah maksimal 20 %.
Obat-obat yang dapat dipergunakan Nicardipin (0,5 6 mcg/kg/menit infus kontinyu),
Diltiazem (5 40 g/Kg/menit drip), nitroprusid (0,25 10 g/Kg/menit infus
kontinyu), nitrogliserin (5 10 g/menit infus kontinyu), labetolol 20 80 mg IV
bolus tiap 10 menit, kaptopril 6,25 25 mg oral / sub lingual. Keseimbangan cairan
dan elektrolit perlu diawasi
33
Kadar gula darah (GD) yang terlalu tinggi terbukti memperburuk outcome pasien
stroke, pemberian insulin reguler dengan skala luncur dengan dosis GD > 150 200
mg/dL 2 unit, tiap kenaikan 50 mg/dL dinaikkan dosis 2 unit insulin sampai dengan
kadar GD > 400 mg/dL dosis insulin 12 unit.
c. Brain : Bila didapatkan kenaikan tekanan intra kranial dengan tanda nyeri kepala,
muntah proyektil dan bradikardi relatif harus di berantas, obat yang biasa dipakai
adalah manitol 20% 1 - 1,5 gr/kgBB dilanjutkan dengan 6 x 100 cc (0,5 gr/Kg BB),
dalam 15 20 menit dengan pemantauan osmolalitas antara 300 320 mOsm,
keuntungan lain penggunaan manitol penghancur radikal bebas.
Peningkatan suhu tubuh harus dihindari karena memperbanyak pelepasan
neurotransmiter eksitatorik, radikal bebas, kerusakan BBB dan merusak pemulihan
metabolisme enersi serta memperbesar inhibisi terhadap protein kinase.Hipotermia
ringan 30C atau 33C mempunyai efek neuroprotektif.
Bila terjadi kejang beri antikonvulsan diazepam i.v karena akan memperburuk perfusi
darah kejaringan otak
d. Bladder : Hindari infeksi saluran kemih bila terjadi retensio urine sebaiknya
dipasang kateter intermitten. Bila terjadi inkontinensia urine, pada laki laki pasang
kondom kateter, pada wanita pasang kateter.
e. Bowel : Kebutuhan cairan dan kalori perlu diperhatikan, hindari obstipasi, Jaga
supaya defekasi teratur, pasang NGT bila didapatkan kesulitan menelan makanan.
Kekurangan albumin perlu diperhatikan karena dapat memperberat edema otak
Penatalaksanaan Stroke Iskemik Akut
Terapi medik stroke merupakan intervensi medik dengan tujuan mencegah meluasnya
proses sekunder dengan menyelamatkan neuron-neuron di daerah penumbra serta
merestorasikan fungsi neurologik yang hilang.
Pengobatan medik dilakukan dengan dua prinsip dasar yaitu
o Pengobatan medik untuk memulihkan sirkulasi otak di daerah yang
terkena stroke, kalau mungkin sampai ke keadaan sebelum sakit.
34
Tindakan pemulihan sirkulasi dan eprfusi jaringan otak disebut sebagai
terapi reperfusi.
o Untuk tujuan khusus ini digunakan obat-obat yang dapat
menghancurkan emboli atau trombus pada pembuluh darah.
Terapi trombolisis
Satu-satunya obat yang diakui oleh FDA sebagai standard ini adalah penggunaan r-
TPA (Recombinant-tissue plasminogen activator) yang diberikan pada penderita
stroke akut dengan syarat-syarat tertentu baik i.v maupun intra arterial dalam waktu
kurang dari 3 jam setelah onset stroke. dengan dosis 0,9 mg/kgBB maksimal 90 mg
(10% diberikan bolus & sisanya infus kontinyu dalam 60 menit). Sayangnya bahwa
pengobatan dengan obat ini mempunyai persyaratan pemberian haruslah kurang dari 3
jam, sehingga hanya pasien yang masuk rumah sakit dengan onset awal dan dapat
penyelesaian pemeriksaan darah, CT Scan kepala dan inform consent yang cepat saja
yang dapat menerima obat ini.
Diharapkan dengan ini, terapi penghancuran trombus dan reperfusi jaringan otak
terjadi sebelum ada perubahan irreversibel pada otak yang terkena terutama daerah
penumbra.
o Terapi reperfusi lainnya adalah pemberian antikoagulan pada stroke iskemik
akut. Obat-obatan yang digunakan adalah heparin atau heparinoid. Obat ini
diharapkan akan memperkecil trombus yang terjadi dan mencegah
pembentukan trombus baru.
o Pengobatan anti-platelet pada stroke akut
o Obat-obat defibrinasi
o Terapi Neuroproteksi, seperti Ca-Channel blocker, antagonis presinaptik dari
Excitatory Amino Acid, obat-obat pensupresi asam arakhidonat dan membran
sel, obat-obat antiradikal bebas.
o CDP-Choline bekerja dengan memperbaiki membran sel dengan cara
menambah sintesa phospatidylcholine, menghambat terbentuknya
radikal bebas dan juga menaikkan sintesis asetilkolin suatu
neurotransmiter untuk fungsi kognitif. Meta analisis Cohcrane Stroke
Riview Group Study(Saver 2002) 7 penelitian 1963 pasien stroke
iskemik dan perdarahan, dosis 500 2.000 mg sehari selama 14 hari
35
menunjukkan penurunan angka kematian dan kecacatan yang
bermakna. Therapeutic Windows 2 14 hari.
o Piracetam, cara kerja secara pasti didak diketahui, diperkirakan
memperbaiki integritas sel, memperbaiki fluiditas membran dan
menormalkan fungsi membran. Dosis bolus 12 gr IV dilanjutkan 4 x 3
gr iv sampai hari ke empat, hari ke lima dilanjutkan 3 x 4 gr peroral
sampai minggu ke empat, minggu ke lima sampai minggu ke 12
diberikan 2 x 2,4 gr per oral,. Therapeutic Windows 7 12 jam.
o Statin, diklinik digunakan untuk anti lipid, mempunyai sifat
neuroprotektif untuk iskemia otak dan stroke. Mempunyai efek anti
oksidan downstream dan upstream. Efek downstream adalah
stabilisasi atherosklerosis sehingga mengurangi pelepasan plaque
tromboemboli dari arteri ke arteri. Efek upstream adalah
memperbaiki pengaturan eNOS (endothelial Nitric Oxide Synthese,
mempunyai sifat anti trombus, vasodilatasi dan anti inflamasi),
menghambat iNOS (inducible Nitric Oxide Synthese, sifatnya
berlawanan dengan eNOS), anti inflamasi dan anti oksidan.
o Cerebrolisin, suatu protein otak bebas lemak dengan khasiat anti
calpain, penghambat caspase dan sebagai neurotropik dosis 30 50 cc
selama 21 hari menunjukkan perbaikan fungsi motorik yang bermakna.
Penatalaksanaan Stroke Hemoragik
Penanganan stroke hemoragik dapat bersifat medik atau bedah tergantung keadaan
dan syarat yang diperlukan untuk masing-masing jenis terapi. Penanganan medik fase akut
dilakukan pada penderita stroke hemoragik dengan menurunkan tekanan darah sistemik yang
tinggi dengan obat-obat antihipertensi yang biasanya short acting untuk mencapai tekanan
darah premorbid atau diturunkan kira-kira 20% dari tekanan darah waktu masuk rumah sakit.
Ada beberapa indikasi untuk tindakan bedah, misalnya volume darah > 55cc, midline shift >
5mm, perdarahan pada ICH, pasien dapat bertahan tapi level fungsional kurang baik.
Pertolongan awal harus bersifat khusus, pada perdarahan otak pertolongan serupa
dengan jenis lain dari stroke (ABC, cegah infeksi, dll). Jika kepastian lokasidan ukuran
perdarahan intraserebral telah jelas pada CT scan, penentuan penyebab perdarahan perlu
36
diketahui karena sangat mempengaruhi prognosis, apalagi jika tindakan pembedahan
direncanakan akan dilakukan.
Larutan Manitol 20-25% merupakan zat yang plaing banyak diapaki : 0,75 1
mg/kgBB bolus, diikuti 0,25-0,5 mg/kgBB setiap 3-5 jam tergantung pada respon klinis.
Komplikasi penggunaan osmotik adalah hipotensi, hipokalemi, gangguan fungsi ginjal karena
hiperosmolaritas, gangguan jantung kongestif dan hemolisis.
Tindakan pembedahan pada perdarahan intraserebral primer, tergantung pada tujuan
tingkat keparahan klinis dan indikasi bedahnya. Tindakan bedah yang dilakukan antara lain
aspirasi sederhana, kraniotomi dan open surgery, evakuasi endoskopik dan aspirasi
stereotaksik.
Pembedahan perdarahan serebelum leih pasti dalam indikasinya dibandingkan
perdarahan supratentorial dan jika dilakukan sesuai indikasi akan menolong hidup penderita.
Indikasi yang jelas yaitu adanya penurunan kesadaran yang disertai dengan kompresi batang
otak yang progresif atau diameter hematom > 3 cm. Jika penderita menurun kesadarannya
dengan disertai hidrosefalus dan diameter hematom < 3 cm, maka tindakan VP
(ventrikulostomi) shunt dapat dilakukan sebagai tindakan awal, dan kemudian observasi
penderita akan menentukan apakah trepamasi serebelar perlu untuk tindakan.
37
DAFTAR PUSTAKA
Kelompok studi serebrovaskuler & Neurogeriatri, PERDOSSI : Konsensus Nasional
Pengelolaan Stroke di Indonesia, Jakarta, 1999.
Kelompok studi serebrovaskuler & Neurogeriatri, PERDOSSI : Guideline Stroke 2000
Seri Pertama, Jakarta, Mei 2000.
National Institute of Neurological Disorders and Stroke: Classification of cerebrovascular
disease III. Stroke 1990, 21: 637-76.
Pusinelli W.: Pathophysiology of acute ischemic stroke. Lancet 1992, 339: 533-6.
Sandercock P, Huub W, Peter S.: Medical Treatment of acute ischemic stroke. Lancet
1992, 339: 537-9.
Widjaja D. Highlight of Stroke Management. Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan,
Surabaya 2002.
Gilroy J. Basic Neurology. Third Edition. Mc Graw Hill. New York, 2000 ; 225 -306
Hinton RC. Stroke, in Samuel MA Manual of Neurologic Therapeutics. Fifth Edition.
Litle Brown and Company Ney York 1995 ; 207 24.
Adam HP, Del Zoppo GJ, Kummer RV. Management of stroke. 2
nd
Ed, Professional
communications inc New York, 2002
Anda mungkin juga menyukai
- Mekanisme BerkeringatDokumen9 halamanMekanisme BerkeringatFebiFascinateD'meean100% (1)
- SabuDokumen4 halamanSabuFebiFascinateD'meean71% (7)
- StimulanDokumen17 halamanStimulanFebiFascinateD'meeanBelum ada peringkat
- Mekanisme HausDokumen12 halamanMekanisme HausFebiFascinateD'meeanBelum ada peringkat
- Mekanisme KeringatDokumen3 halamanMekanisme KeringatFebiFascinateD'meeanBelum ada peringkat
- Creeping EruptionDokumen16 halamanCreeping EruptionMelina SagalaBelum ada peringkat