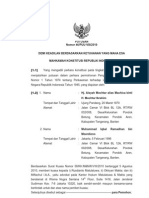Fenomena Ideologi Sesat
Diunggah oleh
Laksmi Widajanti0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
9 tayangan3 halamanHak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
9 tayangan3 halamanFenomena Ideologi Sesat
Diunggah oleh
Laksmi WidajantiHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 3
Fenomena ‘Ideologi’ Sesat
Dr. Mahmudi Asyari
Saya tidak tahu persis apakah tadhliliyyah sebagaimana terma takfiriyyah
(mengkafirkan) yang telah sering kita dengan sudah populer penggunaannya atau tidak.
Namun, yang jelas dalam praktiknya tadhliliyyah sudah sering dijumpai di kalangan
masyarakt.
Tadhlililiyyah yang merupakan derivasi dari kata “dhalla” sebagai lawan dari
kata “ihtada” dalam bahasa Indonesia berarti sesat atau jika merujuk kepada kamus
bahasa Arab salah satunya berarti berjalan tidak di jalan haqq (kebenaran) atau tidak
mendapatkan petunjuk.
Abu Ishaq al-Syatibi, seorang ulama dari kalangan Malikiyyah di mana bukunya
terutama, “Al-Muwafaqat”, dan “Al-I’tisham” banyak menjadi rujukan dalam soal ini,
sulit menentukan definisi sehingga dari dua ungkapan yang dilontarkannya terkesan
kontradiksi. Akan tetapi, jika masalah itu dibandingkan dengan kitab, “Al-I’tisham” di
aliran Hambali (kalau tidak salah tulisan Ibn Taimiyyyah) perbedaan luar biasa akan
terlihat. Sebab, dalam “Al-I’tisham” terakhir semua dilibas habis. Asal dianggap tidak
ada dalil semua bid’ah. Dan, setiap bid’ah masuk neraka.
Pandangan itulah yang kemudian melahirkan ‘ideologi” tadhliliyyah di mana
sasarannya adalah orang-orang yang masih menerima terutama aspek lokalitas di
nusantara ini. Alasannya, bid’ah itu sehingga orang-orang yang ‘ramah’ kepada lokalitas
dilabeli sesat jika tidak kemudian agar lebih keras dilabeli kafir.
Kecuali jika merujuk kepada “Al-I’tisham” karya ulama Hambali, terma yang
dijadikan dasar untuk melabeli orang lain sesat sesungguhnya ada dalam ranah
perdebatan yang sampai sekarang tidak ada kata akhir. Sehingga, semestinya masalah itu
tidak lantas dianggap sebagai ‘hakim’ atau kata akhir mengingat apa yang masuk dalam
ranah itu masuk kategori dzanni (relatif). Bahkan, yang lebih mengenaskan lagi,
pengikut aliran ini sangat menentang apa yang disebut dzikir bersama dengan alasan
Nabi tidak pernah melakukan itu. Katanya, tausiyyah saja. Apa tausiyyah tidak termasuk
dzikir dalam bentuk lain.
Ini sungguh ironi menurut saya. Dan, keironian itu terjadi lantaran tidak bisa
membedakan mana nilai dan mana ibadah yang harus sesuai pakem dan tidak boleh
dirubah. Dzikir pada malam tahun baru atau pada momen tertentu adalah pemberian
nilai bukan ibadah pokoknya. Masalah tidak harus tahun baru memang benar, karena
setiap muslim memang harus berdzikir kapan saja. Namun, jika itu dilakukan dengan
partisipasi massa; apakah sesat? Ya, kalau dianggap sesat jangan ikut saja. Namun, bagi
saya jauh lebih menimbulkan persoalan orang-orang yang menilai orang lain sesat
apalagi dengan kata-kata dengan penuh nyinyiran. Bukankah sikap itu berlawanan
dengan asas hikmah (bijak)?
Oleh sebab itu, setiap pendakwah, harus mencermati betul bahwa dirinya
sebagaimana banyak didengunkan orang, “Nahnu du`at la qudhat!” (kami pendakwah
bukan pemberi kata akhir). Siapa yang dimaksud pemberi kata akhir itu tidak lain adalah
Allah. Jadi, semestinya, masalah yang sesat dan tidak apalagi sampai seperti memonopli
surga bukan ranah manusia termasuk Nabi sekalipun. Ranahnya hanya sebatas
menunjukkan mana yang benar sesuai pemahamannya. Pemahaman pun tergantung
seberapa banyak referensi yang dibaca, seberapa varian, dan seberapa paham. Makin
banyak referensi kemungkinan akan semakin toleran. Namun, jika ingin berpandangan
hitam putih, tidak perlu membaca referensi terutama dari aliran lain. Kalau perlu al-
Quran dan buku Sunnah saja. Dan, akan lebih ‘afdhal’ lagi jika hanya berdasarkan
terjemahan semata. Diakui atau tidak, salah satu sebabk kenapa bagi sekelompok orang
bahwa Idul Adha harus ikut Saudi, menurut saya, akibat terjemahan yang kurang akurat
terhadap sebuah dalil.
Sikap itu sungguh disayangkan mengingat apa yang dinilai kebenaran mutlak itu
sebenarnya juga tidak telepas dari aspek ‘menurut’; menurut guru, menurut ustaz,
menurut Sunnah, dan jenis ‘menurut’ lainnya. Dan, ironinya, ketika memberikan
pendapat kata ‘menurut’ itu tidak mau disebutkan sehingga yang keluar seakan putusan
Allah dan Rasul-Nya. Jika sudah demikian, bukan lagi du’at, tapi hakim sudah.
Berkaitan dengan hal itu, semestinya, para penganut ‘idelogi’ tadhliliyyah itu
mencermati firman Allah dalam surah Al ‘Imran ayat 64 yang artinya, “Katakanlah:
Wahai Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani), marilah (berpegang) kepada suatu kalimat
yang tidak ada perselisihan antara kami (muslimun) dan kamu bahwa kita tidak
menyembah kecuali Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun dan tidak
juga sebagian kita menjadikan yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka
berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-
orang yang berserah diri (kepada Allah)”.
Atas dasar itu, Olaf Schumann, menegaskan bahwa tidak ada masalah antara
Islam dan terutama dengan Yahudi dan Nashrani, karena semua dipersatukan dalam satu
asas, yaitu tunduk (islam) kepada Tuhan. Itulah sebabnya, ketika terjadi saling klaim;
apakah Ibrahim seorang Yahud atau Nashrani, Allah menegaskan bahwa ia bukan
keduanya melain seorang ‘muslim’ yang lurus (hanif). Apabila, terhadap Yahudi dan
Nashrani Allah menegaskan demikian, kenapa itu tidak dijadikan dasar dalam melihat
keberagaman di internal umat Islam sendiri? Toh andaikata memang pasti sesat juga, Ia
Maha Pengampun, dan setiap hamba-Nya berkesempatan masuk surga meskipun bekal
kebajikannya sebesar biji yang sangat kecil sekalipun. Jadi, janganlah seperti Mpok
Rodiyah dalam sinetron Islam KTP yang merasa seperti pemegang ‘kunci’ surga!.
-------------------
DIMUAT DI WAWASAN PADA RABU TANGGAL 25 MEI 2011
Anda mungkin juga menyukai
- Draft RUU Pendidikan Kedokteran Siap Baleg 21 Mar 2011Dokumen29 halamanDraft RUU Pendidikan Kedokteran Siap Baleg 21 Mar 2011Laksmi WidajantiBelum ada peringkat
- Putusan MKDokumen45 halamanPutusan MKLaksmi WidajantiBelum ada peringkat
- Putusan MKDokumen45 halamanPutusan MKLaksmi WidajantiBelum ada peringkat
- Fenomena Ideologi SesatDokumen3 halamanFenomena Ideologi SesatLaksmi WidajantiBelum ada peringkat