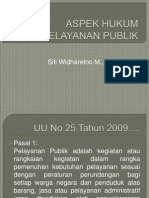Otonomi Daerah
Otonomi Daerah
Diunggah oleh
hamzah ansoriJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah
Diunggah oleh
hamzah ansoriHak Cipta:
Format Tersedia
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada negara yang sedang berkembang yang sektor swasta dan sektor
masyarakat relatif belum maju, sektor pemerintah memegang peranan yang sangat
menentukan. Sektor pemerintah harus bertindak sebagai promotor pembangunan.
Pada saatnya apabila sektor swasta dan sektor masyarakat semakin maju karena
pembangunan, peranan sektor pemerintah secara bertahap mulai berkurang. Tarik-
menarik peranan antara sektor pemerintah dan sektor swasta serta sektor
masyarakat apabila tidak dikelola secara bijak akan dapat menimbulkan berbagai
ketegangan sosial. Dalam hal ini diperlukan pemimpin nasional yang memiliki
dukungan legitimasi politik yang kuat, memiliki kharisma, serta kemampuan
manejerial untuk mengendalikan perubahan.
Prinsip-prinsip good gevernance pada daasarnya mengandung nilai yang
bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur
atau indikator dan ciri-ciri atau karakteristik penyelenggaraan pemerintah yang
baik. Prinsip-prinsip good governence dalam praktik penyelenggaraan negara
sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Dalam kacamata awam, pemerintahan yang baik identik dengan
pemerintahan identik dengan pemerintahan yang mampu memberikan pendidikan
gratis, membuka banyak lapangan kerja, mengayomi fakir miskin. Dengan kata
lain, pemerintah dianggap baik apabila ia mampu melindungi dan melayani
masyarakatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan umum (public service)
yang berkualitas merupakan ukuran untuk menilai sebua pemerintahan yang baik,
sedangkan pelayanan umum yang buruk lebih mencerminkan pemerintahan yang
miskin inovasi dan tidak memiliki keinginan untuk mensejahterakan
masyarakatnya (bad governance).
2
B. Rumusan Masalh
a. Mengetahui Definisi dan Pilar-Pilar Good Gevernance
b. Mengetahui Paradigma Baru Berpemerintahan
c. Mengetahui Hubungan Prinsip Good Governance dengan Otonomi Daerah
d. Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Good Governance
C. Tujuan
Dalam pembahasan makalah ini kami mempunyai tujuan yang diharapkan
bisa terealisasikan oleh kita sebagi cikal bakal penerus pemerintahan daerah
yakni:
1. Diharapkan mampu menjelaskan definisi dan pilar-pilar good governance
2. Diharapakan mempunyai gambaran mengenai paradigma baru pemerintahan
3. Diharapkan mampu menjelaskan hubungan prinsip good governance dengan
otonomi daerah
4. Untuk mempunyai gambaran dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui good
governance
D. Manfaat
Dengan adanya pembahasan makalah yang berkenaan dengan pelaksanaan
otonomi daerah melalui good governance ini semoga khusunya bagi kami untuk
terus berkarya demi terciptanya suatu perubahan dalam sistem pemerintahan di
daerah khususnya di Indonesia ini demi terciptanya kesejahteraan rakyat
begitupun dengan rekan pembaca diharapkan mampu terobsesi dengan isi
makalah yang kami sajikan.
3
E. Landasan Hukum
Dalam pembuatan makalah ini kami terinfirasi dan terketuk hati oleh
beberapa dalil Alquran yang dapat dijadikan landasan hukum, diantaranya sebagai
berikut :
1. Surat Annisa ayat 59
Og^4C 4g~-.-
W-EON44`-47 W-ONOgC -.-
W-ONOgC4 4OcO-
Ojq4 jO- 7Lg` W p)
u7+;N4O4L> O) 7/E* +1NO
O) *.- OcO-4 p)
u7+47 4pONLg`u> *.)
gO4O^-4 @O=E- _ ElgO
OOE= }=O;O4 ECj> ^)_
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2. Surat Al Balad ayat 5
CU=O^4 p }- 4Og^4C
gO^OU4N /4 ^)
Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorangpun yang
berkuasa atasnya?
4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi dan Pilar-Pilar Good Gevernance
Salah satu istilah penting yang muncul ke permukaan dan begitu popular
pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya gerakan Reformasi adalah good
governance. Istilah ini selalu dikutip atau disebut dalam setiap even penting yang
menyangkut masalah pemerintahan, baik dalam pidato-pidato resmi para pejabat
Negara maupun obrolan biasa ditengah kalangan masyarakat umum.
Istilah good governance makin popular seiring dengan gerakan
pembersihan pemerintahan buruk yang ditandai dengan syaratnya tindakan KKN.
Sebenarnya menurut pandangan Masyarakat Transparansi Indonesia wacana good
governance mendapatkan relevansinya di Indonesia paling tidak dengan tiga
sebab utama: Pertama, krisis ekonomi dan krisis politik yang terus berlarut-larut
dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kedua, masih banyaknya
korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan Negara. Dan
ketiga, kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses
demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran bila program tersebut gagal di tengah
jalan.
1
Meskipun istilah ini makin populer ternyata dalam pemaknaan atau
pendefinisiannya berbeda-beda. Setidaknya ada empat pengertian yang menjadi
arus utamanya, yakni pertama, good gevernance dimaknai sebagai kinerja suatu
lembaga, misalnya kinerja suatu pemerintahan Negara, perusahaan atau organisasi
masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengertian ini merujuk pada
arti asli kata geverning yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau
mempengaruhi masalah publik dalam satu negara; kedua, good governance
dimaknai sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi dengan meniscayakan
civic culture sebagai penopang keberlanjutan demokrasi itu sendiri;
5
1
MTI, Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Jakarta: MTI dan AusAID, 2002, hal. 7
ketiga, good governance diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik;
keempat, good governance diartiakan dengan istilah aslinya atau tidak
diterjemahkan karena memandang luasnya dimensi good governance yang tidak
bisa direduksi hanya menjadi pemerintah semata.
B. Paradigma Baru Berpemerintahan
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat sangat dinamis,
bergerak seperti pendulum antara kutub yang sangat berkuasa pada kutub yang
sangat lemah. Pada awalnya, pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat
menjalankan fungsi utama melayani masyarakat yang memberikan kewenangan
kepadanya. Dalam perjalanan waktu, pemerintah menjadi sangat berkuasa.
Kemudian menelan masyarakat yang membentuknya. Masyarakat hanya menjadi
objek kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. Kenyataan tersebut dapat
dilihat secara jelas dalam panggung kehidupan masyarakat dunia sebelum abad
ke-19, pada saat terjadinya pemerintahan kolonialisme ataupun pemerintahan
dengan corak monarki absolut.
Pendulum tersebut kemudian bergeser setelah berkembangnya paham
demokrasi pada awal abad ke-20. Masyarakat yang semula hanya menjadi objek
kekuasaan yang sewenang-wenang, kemudian bangkit dan menungtut hak dan
kewajiban yang seimbang. Pemerintahan demokratis harus dijalankan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Konsep ideal ini, dalam praktiknya banyak mengalami penyimpangan.
Pimpinan politik dan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat
menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme
merajalela dimana-mana. Kekayaan negara dan hasil uang pajak yang dipumgut
dari rakyat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Situasi dan
kondisi semacam ini telah mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan
sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak
menyimpang dari tujuan mulianya.
6
Diberbagai tempat terdapat kecenderungan umum adanya rasa tidak
percaya masyarakat terhadap pemerintah. Dalam berbagai literatur seperti yang
ditulis oleh Peter F. Drucker dalam bukunya The age of Discontinuity telah
digambarkan kemungkinan kebangkrutan birokrasi. Pada sisi lain, Barzelay dalam
bukunya Breaking Throught Bureauracy, menggambarkan bahwa masyarakat
telah bosan pada birokrasi pemerintah yang bersifat rakus dan bekerja lamban.
Osborne dan Gaebler dalam bukunnya Reinveinting Goverment berpendapat
bahwa kegagalan pemerintahan saat ini adalah kelemahan manajemen.
Masalahnya bukan terletak pada apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan cara
pemerintah mengerjakannya.
2
Seiring dengan perubahan paradigma di atas, muncul gerakan baru yang
dinamakan Gerakan Masyarakat Sipil (civil society movement). Inti gerakan ini
adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi lebih mampu dan mandiri untuk
memenuhi sebagian besar kepentingannya sendiri. Konsekuensi logis dari
berkembangnya masyarakat sipil adalah semakin rampingnya bangunan birokrasi
karena sebagian pekerjaan pemerintah dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat
ataupun dilaksanakan melalui pola kemitraan dalam rangka privatisasi. Oleh
karena itu, tidaklah salah apabila Savas mengatakan bahwa privatisasi merupakan
kunci menuju pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian,
ketergantungannya kepada institusi birokrasi pemerintah menjadi semakin
terbatas, dalam arti tercipta ketidaktergantungan relatif (independency relative)
masyarakat terhadap pemerintah.
Perubahan besar yang diharapkan terjadi dalam hubungan antara
pemerintah dan masyarakat ternyata tidak terjadi secara signifikan. Hal ini tidak
dapat dilepaskan dari sifat dan pengertian kata pemerintahan (Goverment), yang
memang harus memerintah. Dengan memerintah, terjadi hubungan yang bersifat
hierarkis menjadi heterarkis, diperlukan perubahan filosofi dan konsep berpikir,
termasuk penciptaan istilah baru yang lebih tepat.
2
Sadu Waistono, Kapita Selekta Penyelenggaraan pemerintah Daerah, Fokusmedia, Bandung,
2003, hlm. 29.
7
Dengan adanya perubahan besar maka akan adanya sebuah antisipasi dan
terjalinlah sebuah hubungan yang begitu signifikan antara yang memerintah dan
yang diperintah.
Berkaitan dengan hal di atas, World Bank ataupun United Nation
Development Program (UNDP) mengembangkan istilah baru, yaitu governance
sebagai pendamping kata goverenment. Istilah tersebut sekarang sangat populer
digunakan dikalangan akademisi ataupun masyarakat luas. Kata governance
kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dalam berbagai kata. Ada
yang menerjemahkan menjadi tata pemerintahan dan ada juga yanng
menerjemahkan kepemerintahan.
Perubahan fungsional berkaitan denagn perubahan fungsi-fungsi yang
akan dijalankan oleh pemerintah pusat, pemrintah daerah ataupun masyarakat.
Adapun perubahan kultural berkaitan dengan perubahan pada tata nilai dan
budaya-budaya yang melandasi hubungan kerja intraorganisasi, antarorganisasi
ataupun ekstraorganisasi.
Diantara ketiga dimensi tersebut, yang akan dianggap paling sulit
berubaha adalah dimensi kultural karena memerlukan waktudan perjuangan terus-
menerus. Perubahan kultural berkaitan erat dengan perubahan tata nilai, pola pikir,
dan pola tindak yang telah tertanam sejak awal.untuk mengendalikan perubahan
kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi (visionary leader)
C. Hubungan Prinsip Good Governance dengan Otonomi Daerah
World Bank mendefinisikan kata governance sebagai The way state power
is used managing economic and sicial resources for development society.
Pengertian ini menggambarkan bahwa governence adalah cara, yakni cara
kekuasaan negara untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna
pembangunan masyarakat. Cara ini lebih menunjukkan pada hal-hal yang bersifat
teknis.
8
Sejalan dengan pendapat World Bank, UNDP mengemukakan definisi
governance sebagai the exercise of political, economic and administrative
authority to manage a nations affair at all levels. Kata gevernance berarti
penggunaan atau pelaksanaan, yaitu penggunaan kewenangan politik, ekonomi,
dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua
tingkatan. Di sini, titik tekannya pada kewenangan, kekuasaan yang syah, atau
kekuasaan yang memiliki legitimasi. Berdasarkan pengertian tersebut, World
Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan
ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih
menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan
negara. Politik governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan
(policy/strategy formulation). Economic governance mengacu pada proses
pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimflikasi pada masalah
pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan
administrative governence mengacu pada sistem implementasi kebijakan.
Menurut UNDP, governance didukung oleh tiga kaki, yaitu politik,
ekonomi, dan administrasi. Kaki pertama adalah tata pemerintahan dibidang
politik dimaksudkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk formulasi
kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi
bersama-sama politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan
tidak hanya pada tataran implementasi yang selama ini terjadi, tetapi mulai dari
formulasi, evaluasi, sampai pada implementasi.
Kaki kedua, yaitu tata pemerintahan dibidang ekonomi, meliputi proses
pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktifitas ekonomi di dalam negeri dan
interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Sektor pemerintah diharapkan tidak
terlampau banyak terjun secara langsung dalam sektor ekonomi karena akan dapat
menimbulkan distorso mekanisme pasar.
9
Adapun kaki ketiga, yaitu tata pemerintahan dibidang administrasi yang
berisi implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.
Menurut UNDP, governence atau tata pemerintahan memiliki tiga domain, yaitu:
1. Negara atau pemerintahan (state)
2. Sektor swasta atau dunia usaha (private soktor)
3. Masyarakat (society)
Ketiga domain tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat. Sektor pemerintah lebih banyak berkecimpung dan menjadi
penggerak aktivitas dibidanmg ekonomi, sedangkan sektor masyarakat merupakan
objek, sekaligus subjek dari sektor pemerintah ataupun sektor swasta. Hal ini
karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi baik dibidang politik, ekonomi,
maupun sosial budaya.
Gevernence yang dijalankan ketiga domain tersebut tidak sekedar jalan
tetapi harus masuk kategori yang baik (good). Perpaduan antara kata good dan
governence menimbulkan kosakata baru, yaitu good governence, yang kemudian
menjadi populer.
3
Pada negara sedang berkembang yang sektor swasta dan sektor
masyarakat ralatif belum maju, sektor pemerintah memegang peranan yang sangat
menentukan. Sektor pemerintah harus bertindak sebagai promotor pembangunan.
Pada saatnya apabila sektor swasta dan sektor masyarakat semakin maju karena
pembangunan, peranan sektor pemerintah secara bertahap mulai berkurang. Tarik-
menarik peranan antara sektor pemerintah dan sektor swasta dan sektor
masyarakat apabila tidak dikelola secara bijak akan dapat menimbulkan berbagai
ketegangan sosial. Dalam hal ini perlu pimpinan nasional yang memiliki
dukungan legitimasi politik yang kuat, memiliki kharisma, serta kemampuan
manejerial untuk mengendalikan perubahan.
3
Wadu Wasistono, Desentralisasi, Demokrasi dan Pembentukan Good Governance, dalam
Syamsudin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta, hlm. 56.
10
D. Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Good Governance
Good gevernance dapat ditinjau sebagai bentuk pergeseran paradigma
konsep goverment (pemerintah) menjadi governance (kepemerintahan). Secara
epistemologis, perubahan paradigma goverment menuju governance berwujud
pada pergeseran mindset dan orientasi birokrasi sebagai unit pelaksana dan
penyedia layanan bagi masyarakat, yang semula birokrat melayani kepentingan
kekuasaan menjadi birokrat yang berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini
didukung pula oleh sebuah ponstulat klasik dalam ilmu pemerintahan yang
mengasumsikan bahwa pemerintah ada karena adanya masyarakat.
Salah satu layanan tersebut adalah penerbitan regulasi yang dapat
menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat. Akan tetapi, sebelum lebih jauh
kita menelaah kiat-kiat dalam menciptakan regulasi yang kondusif, tidak ada
salahnya apabila kita memulainya dengan memahami terlebih dahulu beberapa
konsep dasar dalam kebijakan publik.
Dalam kacamata awam, pemerintahan yang baik identik dengan
pemerintahan identik dengan pemerintahan yang mampu memberikan pendidikan
gratis, membuka banyak lapangan kerja, mengayomi fakir miskin. Dengan kata
lain, pemerintah dianggap baik apabila ia mampu melindungi dan melayani
masyarakatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan umum (public service)
yang berkualitas merupakan ukuran untuk menilai sebua pemerintahan yang baik,
sedangkan pelayanan umum yang buruk lebih mencerminkan pemerintahan yang
miskin inovasi dan tidak memiliki keinginan untuk mensejahterakan
masyarakatnya (bad governance).
Berbicara masalah good governance biasanya lebih dekat dengan masalah
pengelolaan manajemen pemerintahan dalam membangun kemitraan dengan stoke
holder (pemangku kepentingan). Oleh karena itu, good governance menjadi
sebuah kerangka konseptual tentang cara memperkuat hubungan antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam nuansa kesetaraan.
11
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Salah satu istilah penting yang muncul ke permukaan dan begitu popular
pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya gerakan Reformasi adalah good
governance. Istilah ini selalu dikutip atau disebut dalam setiap even penting yang
menyangkut masalah pemerintahan, baik dalam pidato-pidato resmi para pejabat
Negara maupun obrolan biasa ditengah kalangan masyarakat umum.
Meskipun istilah ini makin populer ternyata dalam pemaknaan atau
pendefinisiannya berbeda-beda. Setidaknya ada empat pengertian yang menjadi
arus utamanya, yakni pertama, good gevernance dimaknai sebagai kinerja suatu
lembaga, misalnya kinerja suatu pemerintahan Negara, perusahaan atau organisasi
masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengertian ini merujuk pada
arti asli kata geverning yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau
mempengaruhi masalah publik dalam satu negara; kedua, good governance
dimaknai sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi dengan meniscayakan
civic culture sebagai penopang keberlanjutan demokrasi itu sendiri; ketiga, good
governance diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik; keempat, good
governance diartiakan dengan istilah aslinya atau tidak diterjemahkan karena
memandang luasnya dimensi good governance yang tidak bisa direduksi hanya
menjadi pemerintah semata.
Khususnya dalam pengimplementasian sebuah pelayanan dalam
pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan good governance tentunya harus
diawali dengan pembekalan diri sendiri yang mampu memberikan sebuah
pelayanan yang baik. Pada dasarnya harus berkualitas dan kompeten untuk
mempersiapkan diri dalam melaksanakan otonomi daerah ini. Setelah banyak
pemaparan yang dijelaskan diatas dapat diambil benang merahnya bahwa dalam
mewujudkan good governace harus adanya sebuah rekrutmen yang benar-benar
12
berkulaitas yang mampu dapat mewujudkan suatu tujuan tanpa banyak wacana,
tentunya ketika adanya sebuah rekrutmen para pelayan yang berkualitas dan
kompeten tidak akan banyak alasan klasik yang dapat meruntuhkan suatu
pemerintahan daerah, dan akan jauh dengan yang namanya sebuah KKN.
B. Saran-saran
Saya selaku pemakalah mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat
dalam makalah ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari
semuanya agar makalah ini dapat dibuat dengan lebih baik lagi. Dan mudah-
mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa, umumnya bagi
semuanya.
13
DAFTAR PUSTAKA
MTI, Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Jakarta: MTI dan
Aus AID, 2002.
Waistono, Sadu. Kapita Selekta Penyelenggaraan pemerintah Daerah. Bandung:
Fokusmedi. 2003.
Wasistono, Sadu. Desentralisasi, Demokrasi dan Pembentukan Good
Governance, dalam Syamsudin Haris, Desentralisasi dan Otonomi
Daerah. Jakarta: LIPI Press.
Rosidin, Utang. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia.
2010.
Anda mungkin juga menyukai
- Perbandingan Dari PemerintahanDokumen3 halamanPerbandingan Dari Pemerintahanhamzah ansoriBelum ada peringkat
- Bab IDokumen11 halamanBab Ihamzah ansoriBelum ada peringkat
- Sistem Pemerintahan Negara Menggambarkan Adanya LembagaDokumen12 halamanSistem Pemerintahan Negara Menggambarkan Adanya Lembagahamzah ansoriBelum ada peringkat
- Metode Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan MasyarakatDokumen17 halamanMetode Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Masyarakathamzah ansoriBelum ada peringkat
- Teori Perencanaan Dan PengendalianDokumen6 halamanTeori Perencanaan Dan Pengendalianhamzah ansori100% (1)
- Administrasi Keuangan NegaraDokumen9 halamanAdministrasi Keuangan Negarahamzah ansori50% (2)
- Dasar-Dasar Hukum Administrasi NegaraDokumen9 halamanDasar-Dasar Hukum Administrasi Negarahamzah ansoriBelum ada peringkat
- Aspek Hukum Pelayanan PublikDokumen5 halamanAspek Hukum Pelayanan Publikhamzah ansoriBelum ada peringkat
- Ekologi AdministrasiDokumen43 halamanEkologi AdministrasiNobita Doraemon67% (6)
- Makalah SanriDokumen14 halamanMakalah Sanrihamzah ansori0% (1)
- Ekologi AdministrasiDokumen10 halamanEkologi Administrasihamzah ansori100% (1)
- Pengertian Perbuatan Administrasi NegaraDokumen13 halamanPengertian Perbuatan Administrasi Negarahamzah ansori100% (3)