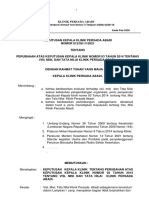Pendidikan Kontekstual Dan Kontekstualisasi Pendidikan
Pendidikan Kontekstual Dan Kontekstualisasi Pendidikan
Diunggah oleh
Renko AjahJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Pendidikan Kontekstual Dan Kontekstualisasi Pendidikan
Pendidikan Kontekstual Dan Kontekstualisasi Pendidikan
Diunggah oleh
Renko AjahHak Cipta:
Format Tersedia
Pendidikan Kontekstual, Kontekstualisasi Pendidikan
Persoalan pendidikan di Indonesia, andai hendak dikatakan dalam satu frasa, maka
itu adalah SISTEM PENDIDIKAN KITA TIDAK KONTEKSTUAL. Titik. Itulah persoalan
mendasarnya, lantas merambat ke mana-mana, bahkan hingga kualitas guru
(semacam apa) juga menjadi tidak terurus. Maka, solusinya juga satu kata:
KONTEKSTUALISASIKAN SISTEM PENDIDIKAN KITA. Titik.
Ada dua persoalan mendasar yang bisa kita sebut sebagai dampak dari salah urus
pendidikan nasional. Pertama, pengangguran yang melimpah. Survei BPS Agustus
2010 bahwa dari 116, 5 juta angkatan kerja, ada 710.00 ber-ijasah sarjana, ada
443.000 lulusan Diploma, yang tidak tau hendak ‘ngapain’ alias tanpa kerja. Bahkan,
tenaga kerja Indonesia hari ini 49,53 persen adalah lulusan Sekolah Dasar.
Kedua, siswa atau rakyat kerap dijadikan korban dalam soal akses hak pendidikan.
Rakyat terus ditindas karena dibatasi meng-akses hak dididik, dengan beragam
bentuk tes ini dan itu. Akibatnya, pendidikan sebagai barang publik menjadi mahal
dan sulit bagi mayoritas warga negeri. Pemerataan pendidikan oleh pemerintah,
sebagai amanat Konstitusi Negara menjadi sekedar mimpi dan mimpi.
Belum tuntas dengan tugas pemerataan penyediaan akses, malahan penguasa hari
ini menerapkan konsep neo-liberalisme dalam dunia pendidikan. Negara didesain
agar membatasi akses publik terhadap hak pendidikan—negara tidak lagi
bertanggung jawab penuh biaya pendidikan—dengan cara-cara halus, yakni dengan
melegitimasi kompetisi (manifestasi paham individualistik) melalui istilah seleksi
masuk!
Dengan seleksi, beban pembiayaan negara jadi berkurang, sebab yang sudah pasti
lulus masuk jumlahnya terbatas. Publik pun dipaksa mengikuti pola pikir anti sosial ini.
Publik diajar saling sikut, harus berkompetisi, otomatis saling mengalahkan, untuk
memperoleh kursi di lembaga pendidikan (Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi),
adalah wajar. Ini jelas akan mengacaukan sistem berbudaya kita. Bahkan,
pembatasan melalui cara halus ini adalah bentuk pelanggaran HAM serius, karena
pendidikan sebagai barang publik adalah hak warga negara, yang mestinya langsung
kita terima tanpa harus ikut seleksi-seleksi diskriminatif itu.
Kontekstualisasi pendidikan adalah solusi
kaitan solusi lepas dari lilitan persoalan pengangguran massal ini. “Pendidikan dalam
Pembangunan”, agar perlunya keterlibatan perguruan tinggi (PT) dalam merancang,
bahkan hingga mengevaluasi jalannya pembangunan di Indonesia, termasuk di
tingkat daerah.
Apalagi, mengingat kini perencanaan pembangunan Indonesia telah dipetakan dalam
enam koridor, sebagai fokus pembangunan sektor. Gagasan agar pembangunan
secara keseluruhan perlu melibatkan PT menjadi relevan, walau mestinya itu tidak
terbatas di lembaga tinggi. Pada tataran pendidikan dasar, mereka juga mestinya
dilibatkan. Dengannya, siswa sudah akan dibiasakan mendesain hidup dan orientasi
pendidikannya sedari awal yang mengarah pada pembangunan potensi alam
Indonesia pada konteks daerahnya, bukan malah diarahkan pada mimpi-mimpi yang
jauh dari konteksnya.
Adalah lucu dan memalukan, kalau-kalau ada di antara kita yang enggan menjadi
petani atau bahkan malu bercita-cita menjadi seorang nelayan handal. Dari sisi
konteks, mestinya itu tidak harus terjadi. Di titik inilah, kita perlu mendesain agar
pendidikan kita mulai dari tingkat dasar hingga tinggi sungguh-sungguh kontesktual,
dalam arti sejalan dengan upaya-upaya pengembangan potensi alam di
lingkungannya.
Bila perlu, secara sederhana (sebagai contoh saja), untuk mereka di Wakatobi, cara
menjala dan memancing ikan dengan metode-metode teruji harus diajarkan dan
masuk dalam kurikulum pendidikan lokal. Bagi mereka yang ada di pedalaman Jawa,
secara sengaja mestinya juga diajarkan bagaimana mencangkul dan atau menanam
padi dengan metode-metode yang bertanggung jawab. Bukan hanya dalam kaitan
bagaimana melakukan sesuatu, bahkan siswa juga perlu diajarkan beragam
pemikiran unik lokal (local wisdom), kaitan cara memaknai hidup dalam konteksnya.
Secara garis besar, Indonesia kini dibagi ke dalam enam wilayah sektor
pembangunan dengan fokus yang berbeda-beda. Sumatera ditetapkan sebagai
sektor atau sentra produksi dan pengelolaan hasil bumi dan energi. Koridor Jawa,
sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Kalimantan sebagai pusat
produksi dan pengelolaan hasil tambang dan lumbung energi.
Koridor Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung
pangan nasional. Koridor Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengelolahan hasil
pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pertambangan nikel. Koridor Papua dan
Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan
nasional.
Dengan pemetaan ini, menjadi keharusan dan kemestian bagi Perguruan Tinggi di
masing-masing wilayah, termasuk berbagai lembaga pendidikan dasar, untuk
mereorientasikan pengembangan kurikulum pendidikannya agar sejalan dengan
tujuan-tujuan pemetaan potensi wilayah yang telah dilakukan pemerintah pusat itu.
perguruan tinggi di daerah juga harus segera mereformasi diri agar jurusan-jurusan
studi yang dikembangan di kampus pun sejalan dengan usaha mengembangkan dan
mengelola potensi daerahnya.
Inilah setidaknya salah satu bentuk menerapkan maksud kontekstualisasi pendidikan
itu, yakni kurikulum lembaga pendidikan secara sengaja, secara baik, dan secara
teratur didesain dalam rangka memaksimalkan potensi alam dengan ilmu
pengetahuan yang bertanggung jawab, itu berarti tidak boleh merusak alam.
Kontekstualisasi kedua adalah pengembangan potensi sumber daya manusia
setempat, atau siswa sesuai dengan, bukan saja searah dengan kebutuhan
mengelola alam sekitar, namun juga sesuai dengan potensi kecerdasan masing-
masing siswa sebagai manusia yang unik.
Penulis berkeyakinan—maklum saja karena penulis beriman bahwa Tuhan Pencipta
itu ada—bahwa bukanlah suatu kebetulan kita lahir di bumi Indonesia, di pulau
Maluku, misalkan, dan dengan potensi kecerdasan tertentu pula. Karena dicipta, dan
tentunya memiliki tujuan, maka adalah penting untuk memahami bahwa keberadaan
kemanusiaan kita di bumi Indonesia (khususnya di tanah Maluku) dengan beragam
potensi alam, termasuk kecerdasan tertentu tidaklah sekedar ada, tanpa maksud dan
tujuan yang suci.
Dengan anggapan ini, maka fungsi pendidikan menjadi jelas, sebagai upaya
memaksimalkan potensi siswa yang bukan saja sesuai dengan kebutuhan
pengembangan potensi alam, namun utama-utamanya juga dalam rangka meng-
eksplorasi kemampuan unik darinya. Di sinilah peran sentral lembaga pendidikan,
yakni mempertemukan dua hal berbeda—namun tidak bisa dipisahkan—itu agar
searah.
Menjadi tugas penting bagi sekolah untuk mendesain kurikulum pendidikan agar
potensi siswa yang unik itu sungguh-sungguh bisa berkembang, sekaligus di saat
yang sama juga bermanfaat bagi pengembangan potensi alam di sekitarnya.
Pendidikan yang memanusiakan siswa adalah pendidikan yang membawa seseorang
menjadi dan berkembangan sesuai dengan potensi kecerdasan yang dimilikinya,
namun juga berguna bagi kemanusiaan.
Bagi siswa, adalah penting untuk paham bahwa kecerdasan yang dianugerahkan ilahi
kepada kita, bukanlah sesuatu yang hanya ada untuk ada, namun tentu itu ada untuk
dimanfaatkan bagi penciptaan situasi lingkungan, di mana kita berada, tampil lebih
baik. Kita harus sadar bahwa potensi kecerdasan itu haruslah membawa manfaat bagi
pengembangan potensi alam dan kelestarian lingkungan di mana kita hidup. Tanpa
kedua itu, kita telah gagal menjadi manusia-manusia yang utuh:
Anda mungkin juga menyukai
- Hakiki PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAIDokumen9 halamanHakiki PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAIRenko AjahBelum ada peringkat
- Mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang STIE Pertiba Pangkalpinang STIE Pertiba PangkalpinangDokumen28 halamanMahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang STIE Pertiba Pangkalpinang STIE Pertiba PangkalpinangRenko AjahBelum ada peringkat
- 1.3.4. Check List Kelengkapan Dan Evaluasi File KepegawaianDokumen1 halaman1.3.4. Check List Kelengkapan Dan Evaluasi File KepegawaianRizki Novi SBelum ada peringkat
- D. Sudiyono, Pengaruh Motivasi, Kompensasi, Dan Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Tirta Investama DC Rungkut)Dokumen10 halamanD. Sudiyono, Pengaruh Motivasi, Kompensasi, Dan Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Tirta Investama DC Rungkut)Renko AjahBelum ada peringkat
- CONTOH SK - VISI, - MISI - KlinikDokumen4 halamanCONTOH SK - VISI, - MISI - KlinikRenko AjahBelum ada peringkat
- Hubungan Kemampuan Efikasi Diri Dan Kemampuan Kependidikan Dengan Kesiapan Menjadi Guru Tik Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika 1Dokumen8 halamanHubungan Kemampuan Efikasi Diri Dan Kemampuan Kependidikan Dengan Kesiapan Menjadi Guru Tik Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika 1Renko AjahBelum ada peringkat
- MOU ESSA Dengan BIDAN JEJARINGDokumen2 halamanMOU ESSA Dengan BIDAN JEJARINGRenko AjahBelum ada peringkat