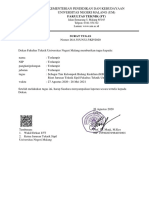Modul 1 Terbaru
Modul 1 Terbaru
Diunggah oleh
Aditya NurJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Modul 1 Terbaru
Modul 1 Terbaru
Diunggah oleh
Aditya NurHak Cipta:
Format Tersedia
Modul 1-1
MODUL 1
1.1. PENDAHULUAN
1.1.1. Siklus hidrologi
Mari kita lihat siklus hidrologi pada Gambar 1.1 berikut ini :
Gambar 1.1 Siklus hidrologi
Gambar 1.1 adalah gambar tentang siklus hidrologi, yang menunjukkan gerakan
atau perjalanan partikel air dari suatu tempat ke tempat lain yang berlangsung terus-
menerus. Mari kita lihat kaitannya dengan kepentingan drainase.
Gerakan infiltrasi atau meresapnya air dari permukaan tanah ke dalam tanah dapat
berlangsung dengan baik apabila dalam tanah cukup tersedia ruang pori . Gerakan ini
terhambat bila ruang pori sangat kecil (secara alami tergantung jenis tanahnya) atau
pori tanah berkurang akibat pemadatan tanah. Terhambatnya peresapan menyebabkan
air tertinggal di atas permukaan tanah, bergerak ke bawah sebagai aliran permukaan
atau diam di atas permukaan tanah sebagai genangan.
Air di atas permukaan tanah bergerak mengikuti kemiringan medan menuju tempat-
tempat rendah dan menuju badan air yang ada, misalnya sungai, danau atau rawa-rawa.
Sepanjang perjalanannya menuju laut air dalam sungai bertambah dari pasokan air
tanah. Hambatan aliran juga ditemui di sungai, antara lain penyempitan alur alami atau
penyempitan akibat adanya jembatan, pembendungan. Penyempitan mengakibatkan
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-2
kenaikan muka air sungai. Pengaruh pembendungan bisa mencapai ribuan meter dan
dapat menyebabkan meluapnya air dari alur sungai.
Aliran dalam tanah, khususnya air tanah dangkal bergerak dengan kecepatan sangat
lambat melalui ruang-ruang di antara partikel tanah. Tergantung pada kondisi
geologinya, air tanah dapat muncul ke permukaan tanah disebut mata air dan mengalir
membentuk sungai. Pada kondisi muka air tanah lebih tinggi daripada dasar sungai, air
tanah akan merembes dan masuk mengisi sungai melalui tebingnya. Dan sebaliknya,
apabila muka air di sungai, di waduk atau tampungan air lainnya lebih tinggi dari muka
air tanah, maka air akan meresap dan bersatu dengan air dalam tanah. Jadi ada
hubungan antara air tanah dan air permukaan.
Dalam kondisi ekstrim ada kemungkinan alur sungai tak mampu menampung
limpasan permukaan, sehingga terjadilah peluapan yang disebut banjir. (Catatan : dalam
ilmu keairan debit banjir diartikan sebagai debit yang lebih besar dari debit normal, dan
tidak selalu berarti meluap dari alur sungai).
Dalam perjalanan partikel air baik di atas permukaan tanah atau dalam tanah, aliran
dapat terhambat secara alami atau akibat campur tangan manusia. Sebagai contoh,
aliran permukaan terhambat karena adanya tumbuh-tumbuhan, relief permukaan bumi,
bangunan, timbunan atau cekungan di permukaan tanah. Hambatan di permukaan tanah
dapat menyebabkan genangan. Di bawah permukaan tanah aliran air tanah dapat
terhambat antara lain karena pemadatan atau peristiwa/proses geologi, sehingga aliran
dapat berubah arah. Contoh lain: pemompaan memaksa air berkumpul ke satu titik
untuk dipompa keluar dari tanah.
1.1.2. Pemanfaatan dan pengendalian air
Manusia berhubungan dengan air untuk dua kepentingan, pertama air untuk
dimanfaatkan dan kedua air yang perlu dikendalikan agar tidak merugikan kehidupan
manusia. Manusia dan makhluk hidup (selain yang hidup dalam air) membutuhkan air
dengan kualitas tertentu dalam jumlah terbatas /secukupnya.
Air tawar diperoleh dari sumber air yang ada dipermukaan tanah seperti sungai,
danau dan rawa, serta dari bawah permukaan tanah, yaitu air tanah dangkal dan air
tanah dalam. Sungai merupakan sumber air permukaan yang potensial. Sungai yang
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-3
berair sepanjang tahun disebut sungai perenial. Meskipun debitnya bervariasi dan
berfluktuasi sepanjang tahun, dapat diupayakan untuk bisa dimanfaatkan, antara lain
dengan membuat bendung untuk meninggikan muka air agar air dapat mencapai sawah,
waduk untuk menyimpan air saat hujan dan memanfaatkannya pada musim kemarau,
pompa untuk mengangkat air dari muka air yang rendah ke tempat yang lebih tinggi,
dsb.
Dalam lingkup Daerah Pengaliran Sungai (DPS), kebutuhan air cukup besar untuk
berbagai kebutuhan; air untuk perkotaan, daerah pertanian, industri dlsb. Kualitas air
permukaan sangat rawan terhadap pencemaran dan masuknya hasil erosi permukaan,
sedang air dari segi kualitas lebih terlindung dari pencemaran, kecuali bila ada
perembesan polutan.
Manusia atau makhluk hidup lainnya dan tumbuh-tumbuhan, membutuhkan air
dalam jumlah secukupnya. Selain tumbuhan air, tumbuhan lain akan terganggu
pertumbuhannya (bahkan busuk lalu mati) bila air tergenang cukup lama. Air dalam
tanah juga menimbulkan masalah pada kegiatan konstruksi apabila muka airnya tinggi.
Aliran partikel air di kawasan permukiman mempunyai fenomena yang hampir
serupa. Air sulit meresap ke dalam tanah karena adanya bangunan rumah, bangunan
gedung, jalan dsb. Aliran dalam saluran drainase juga bisa mengalami hambatan akibat
Pekerjaan drainase mencakup pekerjaan pengendalian air permukaan yang berlebih
(banjir, genangan) dan pengaturan muka air di sungai serta pengendalian air tanah.
Pekerjaan drainase di suatu wilayah dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:
o Drainase basin (basin drainage)
o Drainase perkotaan/permukiman (Urban drainage).
Drainase basin (Basin drainage)
Pekerjaan drainase basin menyangkut pengaturan aliran sungai meliputi
pengendalian debit dan muka air sungai dalam suatu daerah pengaliran sungai atau sub
daerah pengaliran sungai. Aliran sungai meluap dari alurnya karena kapasitas sungai
tidak mampu melewatkan debit banjir saat itu.
Dalam skala DPS, sungai-sungai yaitu sungai utama (sungai induk, main stream)
dan anak-anak sungai (tributaries) merupakan drainase alam yang berfungsi
mengalirkan air dari DPS-nya ke laut. Banjir ditimbulkan oleh sungai-sungai yang pada
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-4
hujan tertentu alurnya tidak mampu melewatkan debit banjir. Banjir suatu sungai
disebabkan oleh :
Pengendapan di alur sungai mengurangi kapasitas alir sungai.
Pengaruh air balik dari sungai utama masuk ke anak-anak sungai atau dari laut
masuk ke sungai utama/induk, sehingga muka air naik melampaui tebing sungai.
Hambatan di alur sungai, misalnya penyempitan penampang sungai (alami atau
karena adanya bangunan, belokan dlsb.)
Bencana banjir yang ditimbulkan oleh sungai dapat mencakup ratusan hektar
lahan dan kerusakan yang ditimbulkan meliputi kerusakan lahan produktif,
permukiman, bangunan-bangunan di darat dan di sungai, prasarana transportasi,
kerugian harta benda, hewan ternak dsb termasuk adanya korban jiwa.
Penanggulangan banjir yang disebabkan oleh sungai banyak ragamnya, termasuk
dalam pekerjaan teknik sungai antara lain pembuatan tanggul, normalisasi sungai,
pembuatan waduk pengendali banjir dsb. yang tidak dibahas dalam matakuliah Drainase
ini. Pekerjaan penanggulangan banjir dalam hal ini disebut basin drainage.
Banjir yang terjadi dapat masuk dalam wilayah kota/permukiman karena sungai ybs.
mengalir dekat atau melalui kota tersebut., disebut sebagai banjir makro. Dalam
penanganannya, harus dipastikan kapasitas alur sungai tersebut harus dapat menampung
debit banjir dengan periode ulang tertentu.
Drainase perkotaan/permukiman
Pekerjaan drainase yang menyangkut pengaturan pembuangan air hujan dan/atau air
limbah dalam wilayah suatu kota/permukiman, disebut juga sebagai urban drainage.
Drainase lapangan terbang, daerah industri, pelabuhan dalam lingkungan perkotaan
termasuk dalam kategori ini, dengan cara penanggulangan yang tidak jauh berbeda.
Dalam lingkup perkotaan atau permukiman, air bersih (hasil olahan air sungai di
instalasi pengolahan air, water treatment plant) kita peroleh dari PAM untuk rumah
tangga, ± 30% yang habis terpakai, sedangkan sisanya terbuang sebagai limbah cair
rumah tangga antara lain buangan dari kamar mandi, sisa cucian dan dari dapur serta
sisa lainnya. Air buangan rumah tangga dapat mengandung deterjen/sabun, sisa-sisa
minyak dari dapur dsb. Air untuk industri, sebagian air digunakan untuk proses,
sebagian untuk pendingin. Sisa proses berupa limbah, dapat berupa limbah organik
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-5
(contoh : limbah pabrik tahu, pabrik tapioka, dsb.) atau limbah yang mengandung zat-
zat kimia sisa proses tersebut (limbah pabrik tekstil dsb). Air sisa irigasi terbuang ke
sungai-sungai dalam keadaan berbeda dengan air yang disuplai, karena telah
mengandung sisa-sisa pupuk dan pestisida. Air buangan yang berasal dari rumah-tangga
/ permukiman, dari pabrik dan dari daerah pertanian / sawah bila mengandung zat-zat
yang berbahaya bagi kesehatan, tidak kita harapkan berada di sekitar kita.
Dengan demikian ada beberapa macam air yang perlu dikendalikan di wilayah
perkotaan/permukiman, yaitu :
a. Air limbah (buangan) dari rumah tangga, fasilitas umum, industri dsb yang
disebut juga sebagai limbah perkotaan atau limbah domestik. Air sisa irigasi
termasuk juga sebagai air limbah.
b. Air limpasan hujan atau disebut air berlebih (excess water)
c. Air tanah.
Pekerjaan yang berurusan dengan pembuangan air limbah dan air berlebih di suatu
tempat disebut drainase perkotaan/permukiman atau urban drainage.
Jaringan saluran drainase dalam suatu kota atau suatu wilayah kota belum tentu
dalam kondisi tertata baik yang menjamin kelancaran pengaliran air. Air hujan yang
tidak dapat mengalir dengan baik, akan meluap dari saluran dan menggenangi lahan di
sekitarnya. Orang awam menyebutnya sebagai banjir lokal. Uraian lebih lengkap dapat
dilihat pada Modul 3.
1.1.3. Pengertian banjir, genangan dan drainase
Ada beberapa pengertian mengenai banjir. Suatu sungai atau saluran disebut banjir
apabila air sungai/saluran meluap dari alurnya, melimpah ke daerah rendah, meluas dan
menimbulkan gangguan pada lingkungan, kerusakan-kerusakan fisik dan menghambat
kegiatan sosial dan ekonomi. Dari pandangan hidrologi banjir yang terjadi di suatu
sungai apabila debit yang mengalir lebih besar dari debit rata-rata atau debit normal
sungai tersebut. Terjadinya banjir dikaitkan dengan frekwensi kejadiannya. Debit
maksimum (rata-rata) yang terjadi 1 × dalam 1 tahun disebut debit banjir tahunan.
Banjir yang terjadi 10 tahun sekali disebut banjir menengah, sedang banjir yang terjadi
50 tahun sekali disebut banjir besar. Selama aliran banjir tetap berada dalam alur sungai
tidak menjadi masalah. Apabila kapasitas sungai tidak
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-6
mampu menampung aliran banjir, sehingga terjadi peluapan dan genangan, maka perlu
segera ditangani.
Genangan, adalah air yang tertahan di suatu tempat dan tidak tersalur dengan cepat
ke pembuangan (saluran, sungai, laut). Genangan dapat terjadi beberapa saat setelah
hujan berhenti, beberapa menit, jam atau bahkan dapat berlangsung berhari-hari,
tergantung pada jenis tanah dan kondisi muka air di pembuangan akhirnya.
Daerah/lahan tergenang permanen disebut rawa-rawa.
1.1.4. Maksud dan tujuan drainase
Telah disampaikan di atas, bahwa ada dua macam air yang perlu dikendalikan
pengaliran dan pembuangannya, yaitu air limbah dan air berlebih. Air berlebih dapat
berupa air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah dan tak tertampung di sungai atau
saluran sehingga menimbulkan banjir/genangan. Air tanah yang ke luar ke permukaan
menggenangi dan merusak bangunan (misalnya menggenangi jalan raya), atau air tanah
dangkal yang permukaannya relatif tinggi, sehingga mengganggu lingkungan (sanitasi
terganggu, pertumbuhan tanaman terganggu) dan menghambat pekerjaan konstruksi
bangunan.
Dampak pada lingkungan yang ditimbulkan oleh sistem drainase yang buruk :
1. Air limbah yang tertahan di saluran atau di tempat-tempat yang rendah menimbulkan
bau busuk, warna yang tidak sedap dipandang, mengandung bibit penyakit dan zat-
zat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
2. Genangan, selain menjadi sarang nyamuk, merusak estetika lingkungan, sarana
penyebaran penyakit (karena sanitasi terganggu), mengganggu pertumbuhan
tanaman, merangsang tumbuhnya tanaman pengganggu di saluran atau di rawa-rawa.
Genangan menimbulkan kerugian materiil, menghambat kegiatan ekonomi dan
sosial, menghambat kelancaran lalu lintas dan merusak sarana dan prasarana
perkotaan (bangunan, jalan dan sebagainya).
3. Air berlebih yang tertahan dalam badan jalan, yaitu dalam konstruksi perkerasan
jalan atau lapangan terbang dapat menurunkan stabilitas jalan.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka maksud dan tujuan pembuangan air
limbah dan air berlebih (selanjutnya disebut pekerjaan drainase) adalah :
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-7
1. Mengalirkan air limbah dan/atau air berlebih secara cepat dan aman ke tempat
pengolahan air limbah (bagi air limbah) dan pembuangan akhir atau badan air
penerima bagi air berlebih (limpasan hujan) untuk menghindarkan terjadinya :
banjir
genangan air pada permukiman atau lahan produktif
erosi lapisan tanah dan endapan-endapan
kerusakan dan gangguan fisik, kimiawi dan biologi terhadap lahan atau
lingkungan aktif dan produktif, agar kesehatan lingkungan tetap terjaga, estetika
terpelihara baik, komunikasi dan lalu lintas ekonomi dan sosial tidak terhambat
2. Mengeringkan lahan yang tergenang atau yang jenuh air dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya agar sanitasi dapat berjalan dengan baik, dan tanaman dapat
tumbuh tak terganggu.
3. Mengusahakan agar air tidak tertahan di dalam badan jalan/perkerasan agar
kestabilan konstruksi jalan tetap terjaga.
1.1.5. Macam-macam pekerjaan drainase
Berkaitan dengan tujuannya dan obyeknya dalam mengatasi air limbah dan atau air
berlebih, pekerjaan drainase meliputi beberapa macam. Dalam mata kuliah Drainase
(PS-1379) ini, jenis pekerjaan drainase yang dibahas meliputi drainase permukiman/
perkotaan, drainase jalan raya, drainase lapangan terbang dan drainase lahan.
1. Drainase permukiman/perkotaan.
Lingkup pekerjaannya adalah mengatur pembuangan air limbah dan air hujan di
daerah permukiman/perkotaan
Berkenaan dengan macam air yang perlu dibuang, ada dua alternatif sistem yang
dapat dipilih, yaitu :
Sistem terpisah, di mana air limbah (domestik, industri) dialirkan dalam suatu
jaringan saluran menuju tempat pengolahan air limbah sebelum dibuang ke
perairan umum (sungai, danau, laut), sedang air hujan dialirkan dalam jaringan
saluran lain yang terpisah dan dapat dibuang secara langsung ke perairan umum.
Sistem tercampur, di mana air limbah dan air hujan dialirkan bersama-sama dalam
suatu jaringan saluran drainase, dan langsung dibuang ke perairan umum.
2. Drainase jalan raya
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-8
Lingkup pekerjaannya adalah mengupayakan agar air hujan atau air tanah tidak
menggenang di atas permukaan jalan dan tidak bertahan dalam lapisan perkerasan
jalankarena dapat menurunkan kestabilan konstruksi jalan.
3. Drainase lapangan terbang
Maksud dan tujuannya serupa dengan drainase jalan raya. Ada dua cara untuk
mematus lahan lapangan terbang; yang pertama dengan membuat saluran-saluran
dan pembuangan seperti drainase permukiman, yang kedua dalam hal pembuangan
tidak dapat dilakukan secara langsung, air hujan ditampung sementara dalam kolam
penampung, untuk selanjutnya dibuang apabila kondisi muka air di saluran
pembuangan akhir sudah cukup rendah.
4. Drainase lahan
Drainase lahan, mengatur pembuangan air berlebih pada suatu lahan, baik yang
berada di atas permukaan lahan, maupun yang berada di dalam tanah, termasuk
mengatur kedalaman muka air tanah.
Drainase lahan pertanian termasuk dalam kelompok ini, namun tidak dibahas dalam
materi kuliah drainase ini. Penjelasan mengenai drainase lahan pertanian dapat
diperoleh di mata kuliah Irigasi. Dalam materi perkuliahan Drainase, lahan yang
didrain/dipatus berupa lahan di mana tidak dikehendaki adanya saluran-saluran
terbuka di permukaan tanah karena dapat mengganggu aktivitas di atasnya, seperti
lapangan sepak bola, lapangan golf dan sebagainya.
Menurut cara pengalirannya sistem drainase dapat dibedakan atas :
a. Sistem gravitasi, aliran mengandalkan perbedaan tinggi muka air di hulu dan di
hilir. Hal ini terkait dengan kemiringan medan yang menentukan kemiringan
saluran serta ketinggian muka air di pembuangan akhir.
b. Sistem pompa, dilakukan apabila pengaliran secara gravitasi tidak dapat dilakukan
sehubungan muka air di hilir (di pembuangan) lebih tinggi daripada muka air di hulu
(di saluran).
Seperti halnya dengan drainse lapangan terbang yang menggunakan kolam
penampungan sementara, pada sistem drainase permukiman hal tersebut dapat juga
dilakukan. Kolam penampungan sementara disebut dengan busem (bouzem, retarding
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-9
basin).
1.1.6. Pola umum sistem drainase
Pada dasarnya prinsip drainase mengikuti pola drainase alam, yaitu sungai.
Saluran-saluran kecil yang menerima air hujan dari luasan kecil, bersama-sama dengan
saluran kecil lainnya bergabung dalam saluran yang lebih besar, demikian seterusnya,
dan selanjutnya dibuang ke pembuangan akhir (outfall). Pembuangan akhir dapat
berupa saluran drainase dari sistem yang lebih besar, sungai, danau, rawa, atau laut.
Perbedaan dengan sungai alam, saluran drainase buatan tidak memiliki sifat yang
kompleks seperti halnya dengan sungai. Pola yang umum jaringan saluran drainase
adalah sebagai berikut:
Gambar 1.2. Pola jaringan saluran drainase
Pola jaringan drainase disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah permukiman
yang direncanakan. Lebih detail dapat dilihat pada Modul 3 (Drainase Permukiman).
1.1.7. Komponen alam yang diperhitungkan dalam perencanaan drainase
Perencanaan drainase dibuat dengan mempertimbangkan komponen alam di tempat
yang bersangkutan :
1. Tanah dan air tanah
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-10
Jenis tanah berkaitan dengan kemampuan peresapan air (menentukan koefisien
pengaliran), ketahanan terhadap gerusan air (menentukan koefisien kekasaran
saluran), dan kedalaman muka air tanah (tampungan dalam tanah, rembesan
saluran).
2. Topografi
Dari garis kontur pada peta topografi daerah, dapat diketahui relief permukaan
medan dan kemiringan medan. Pada perencanaan drainase perkotaan/permukiman,
drainase lahan dan drainase jalan raya/lapangan terbang, dengan bantuan peta
tersebut dapat ditentukan batas daerah pematusan suatu saluran, dan dapat dibuat
jaringan saluran drainase, dan lokasi bangunan-bangunan pelengkap. Dengan peta
topografi dapat dilihat daerah yang tergenang banjir. Dengan bantuan garis kontur
dapat diperkirakan kemiringan saluran yang memenuhi syarat pengaliran air buangan
yang aman.
3. Hidrologi
Kondisi hidrologi suatu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lain tergantung
karakteristik iklim masing-masing. Tersedia banyak metode untuk menghitung
besarnya debit saluran berdasarkan curah hujan pada suatu periode ulang tertentu
sebagai dasar perencanaan dimensi saluran.
4. Penggunaan lahan
Penggunaan lahan atau penutupan lahan menentukan banyaknya air yang mampu
diserap tanah. Dalam perhitungan hidrologi kondisi ini digambarkan dalam koefisien
pengaliran, C.
5. Kondisi pembuangan akhir
Pembuangan akhir merupakan faktor penting yang menentukan sistem pembuangan
air dari saluran. Muka air di sungai dipengaruhi oleh fluktuasi debit sepanjang
waktu, saat musim hujan muka air tinggi dan saat musim kemarau muka air rendah.
Muka air laut dipengaruhi oleh pola pasang surut. Saat pasang ada kemungkinan sulit
melakukan pengaliran secara gravitasi (di dataran yang landai). Muka air di danau
atau rawa relatif tidak banyak berubah.
1.2. TANAH DAN AIR TANAH
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-11
1.2.1. U m u m
Kelancaran suatu sistim drainase di suatu wilayah tidak lepas dari kondisi tanah dan
kedalaman muka air tanah. Besarnya limpasan permukaan (run-off), tergantung pada :
1. Kemiringan lahan
2. Relief permukaan lahan dan penutupan lahan atau penggunaan lahan
3. Struktur tanah
4. Kedalaman muka air tanah
5. Penutup permukaan lahan
Pada permukaan yang kemiringannya besar, air permukaan mengalir lebih cepat
menuju sungai atau saluran, sebaliknya pada permukaan lahan yang landai diperlukan
waktu yang lebih panjang untuk mencapai sungai atau saluran, sehingga ada
kemungkinan terjadi genangan. Pada kemiringan lahan yang besar, sedikit kesempatan
bagi air untuk meresap ke dalam tanah, sedang pada kemiringan yang landai, peresapan
lebih mudah.
Relief permukaan atau bentuk permukaan lahan menentukan kecepatan aliran dan
besarnya limpasan permukaan. Pada permukaan yang licin, misalnya pada jalan atau
lapangan terbang dari aspal, aliran lebih cepat dibanding dengan aliran di atas
permukaan yang bergelombang, di mana aliran terhambat oleh permukaan yang tidak
rata untuk mencapai tempat yang lebih rendah. Air yang mengalir di atas permukaan
yang licin lebih cepat dibanding dengan air yang mengalir di atas lapangan golf yang
berumput, atau di atas kebun jagung, apalagi di hutan yang beragam tumbuhannya.
Limpasan permukaan di atas tanah yang porus, lebih sedikit dibanding limpasan di
atas tanah yang kedap seperti tanah liat atau tanah yang mengandung tanah liat. Pada
tanah yang porus air mudah berinfiltrasi mengisi pori-pori tanah, sedang tanah liat sulit
dilalui air, sehingga lebih banyak air yang menjadi aliran permukaan. Di kota yang
sudah dipenuhi bangunan, apalagi bila banyak bangunan bertingkat berpondasi tiang
pancang, tanah menjadi lebih mampat dan padat. Hal ini mempengaruhi aliran air dalam
tanah, sehingga ruang pori dalam tanah tidak cukup menampung resapan air.
Pada kondisi muka air tanah yang dangkal, tidak banyak air yang dapat tertampung
dalam lapisan tanah di atas permukaan muka air tanah sampai kondisi jenuh tercapai.
Sebaliknya apabila muka air tanah cukup dalam, tanah dapat menyimpan air lebih
banyak
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-12
Kondisi penutupan permukaan tanah sangat mempengaruhi banyaknya air yang
meresap ke dalam tanah. Air limpasan mengalir dalam jumlah besar apabila aliran
tidak mendapat hambatan yang cukup pohon-pohonan, dan tumbuhan lainnya. Tidak
ada yang sebaik hutan-hutan tropis dalam menahan laju aliran permukaan. Terasering
yang dibuat untuk memperkecil kemiringan medan, hanya sedikit mengurangi erosi
permukan. Di daerah yang sudah terbangun, permukaan tanah sudah ditutupi oleh
rumah, jalan raya, lahan parkir dll menggantikan tumbuh-tumbuhan penutup lahan.
Selain menjadikan permukiman atau kota menjadi lebih gerah (panas), air lebih sulit
untuk meresap ke dalam tanah, sehingga potensi terjadinya genangan lebih besar.
Sedikit lahan berumput di tepi jalan, dapat menghambat aliran permukaan yang
membawa partikel tanah masuk ke dalam saluran drainase. Pekarangan yang ditanami
rumput dan tanaman hias akan berarti dalam mengurangi jumlah air yang masuk ke
dalam saluran drainase di depan rumah kita dibanding dengan pekarangan yang tertutup
paving.
1.2.2. Air tanah dan perencanaan kapasitas saluran drainase
Air tanah dangkal berhubungan dengan dengan muka air di sungai atau saluran.
Apabila muka air tanah lebih rendah daripada muka air di sungai atau saluran, maka
terjadi aliran dari sungai/saluran ke air tanah (influent), pada kondisi sebaliknya terjadi
aliran dari muka air tanah ke sungai atau saluran (efluent). Hal seperti ini terjadi pula
pada saluran drainase. Perhatikan saluran drainase di kampus ITS. Di beberapa saluran,
di laguna atau di lahan-lahan yang rendah terdapat genangan air meskipun tidak terjadi
hujan. Kemungkinannya adalah : muka air tanah cukup tinggi sehingga merembes ke
saluran, tanah dasar adalah lempung sehingga sulit ditembus air. Dengan demikian,
pada daerah di mana muka air tanah relatif tinggi, perlu diestimasi tambahan air tanah
pada kapasitas saluran drainase.
Perhatikan laguna yang ada di kampus ITS, hampir sepanjang tahun terdapat
genangan di dalamnya, seperti halnya di saluran. Hal ini mengurangi kapasitas
tampungan. Pada musim hujan kondisi ini perlu diantisipasi dengan sistem operasional
pompa, sedemikian sehingga saat dibutuhkan ruang untuk aliran yang datang dari
saluran-saluran, laguna sudah mempunyai tempat untuk tambahan air.
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-13
1.2.3. Klasifikasi tanah menurut sifat kelulusan airnya
Menurut kemampuan tanah untuk meluluskan air, tanah diklasifikasikan
menjadi:
Tanah pervious (lulus air)
Prosentase pori dalam tanah besar, sifat transmisi tanah ini baik, tahanan
terhadap aliran vertikal kecil, kehilangan energi disebabkan oleh aliran
horizontal. Tanah jenis ini didominasi oleh partikel berbutiran kasar. Adanya
kandungan bahan organik membuat tanah menjadi gembur dan mudah
meluluskan air. Pori-pori dalam tanah dapat terbentuk oleh akar tumbuhan atau
binatang (misalnya cacing). Pori macam ini disebut 'biopores".
Tanah semi pervious (semi lulus air)
Sifat transmisi relatif kurang baik. Aliran horizontal sampai dengan jarak
tertentu dapat diabaikan. Tahanan terhadap alian vertikal tak dapat diabaikan.
Tanah Impervious (kedap air)
Sifat transmisi sangat buruk, tahan vertikal besar, aliran horizontal diabaikan.
Dalam istilah pertanian, tanah dengan sifat-sifat ini disebut "tanah berat", karena
pengolahannya tidak mudah. Pada musim kemarau tanah jenis ini kering dan
retak-retak. Kehilangan air besar di awal musim hujan, namun setelah hujan
berlangsung, sulit menyerap air lagi, karena pori-pori tanah yang kecil sudah
dipenuhi oleh air (jenuh). Apabila terjadi genangan, maka genangan akan
bertahan cukup lama apabila evaporasi berjalan lambat.
Dalam perhitungan hidrologi kondisi struktur tanah merupakan salah satu faktor
yang diperhitungkan dalam koefisien pengaliran (C).
1.2.4. Profil tanah dan air dalam tanah
Profil tanah menurut morfologinya tersusun menjadi beberapa lapisan tanah dengan
sifat porositas (kelulusan air) seperti pada gambar di bawah ini :
Top soil Sangat permeabel, tebal 20 – 30 cm
Sub soil permeabel sedang
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-14
Sub stratum impermeabel
Gambar 1.3. Profil tanah menurut morfologinya
Tanah top soil (tanah atas), gembur, subur karena mengandung banyak bahan organik
dan bersifat erosif (mudah tererosi). Besarnya laju erosi tanah tergantung pada
parameter erodibilitas, yaitu jenis tanah, intensitas hujan, panjang dan kemiringan
lereng, serta perlakuan terhadap tanah.
Pada tanah terbuka potensi untuk tererosi lebih besar, karena tak ada yang
melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan, dan kecepatan aliran dipermukaan
tanah menjadi tinggi, terutama apabila kemiringan lahan besar.
Tumbuh-tumbuhan tidak memerlukan air lebih dari yang dibutuhkan untuk tumbuh
dengan subur. Kelebihan air justru membuat akar menjadi busuk sehingga tumbuhan
mati. Adanya genangan menunjukkan tanah dalam keadaan jenuh air. Tanaman berakar
pendek cepat mati karena akarnya membusuk.
Profil tanah dan kandungan air dalam tanah dapat dilihat pada Gambar 1.4. Tinggi
air kapiler tergantung pada jenis tanah. Tebal tipisnya lapisan tergantung kondisi
geologi setempat. Tinggi kapiler pada tanah silt dapat mencapai 2000 mm, sedang tanah
jenis pasir kasar tinggi kapiler kurang dari 500 mm s/d 195 mm. Untuk zone jenuh
dekat permukaan tanah, pengeringan airnya menjadikan permasalahan pada konstruksi
jalan atau lahan, sehingga perlu diatasi dengan teknik drainase bawah permukaan. Lihat
di Modul 4 dan 5.
Ketebalan dari permukaan tanah sampai setebal
akar
Soil water zone tanaman. Lapisan ini tiak jenuh air kecuali saat
infiltrasi tinggi
Gravitional water zone Zone ini disebut juga intermideate zone. Air
turun kebawah akibat gaya gravitasi. Tebal
lapisan dapat mencapai > 100 m.
Tebal lapisan ini sampai kenaikan air kapiler.
Pada kondisi seimbang tekanan pada tanah je-
Cappilarry zone nuh sama dengan tekanan atmosfir.
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-15
------------ Water table ------------------------
Saturated zone Zone ini jenuh air. Air tersimpan di bawah
tekanan hidrostatis seperti air di waduk
Gambar 1.4 Profil tanah menurut kandungan air dalam tanah
1.2.5. Sifat-sifat tanah
Beberapa sifat tanah yang perlu diketahui dan berkaitan dengan masalah drainase
adalah :
1. Angka pori (void ratio, e)
Vv
e (1.2.1)
Vs
2. Porositas (porosity, ne)
V
ne v (1.2.2)
V
3. Hubungan antara e dan ne
n e
e dan ne (1.2.3)
1 n 1 e
di mana Vv = volume pori
Vs = volume butir
V = volume tanah
4. Koefisien rembesan (koefisien permeabilitas, hidrolik konduktivitas, k),
didefinisikan sebagai kecepatan aliran melalui material permeabel dengan
suatu kemiringan hidrolik sama dengan 1.
Angka ini dapat diperoleh dari percobaan Darcy, yaitu tentang gerakan
aliran bawah tanah :
Q k i A (1.2.4)
Q
atau k
i A
q
untuk per satuan lebar : q
iD
di mana A = luas penampang B D
untuk per satuan lebar A = 1 D
D = tebal lapisan tanah
Harga k tergantung pada geometri butiran, kejenuhan tanah, temperatur dan
adanya retakan-retakan di tanah. Temperatur mempengaruhi harga k karena
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-16
menyebabkan viskositas air berkurang, sehungga meningkatkan harga k.
Untuk lapisan tanah yang dalam, pengaruh temperatur diabaikan.
Tabel 1.1. Perkiraan harga k
Jenis tanah Harga k (mm/hari)
Coarse gravely sand 10 – 50
Medium sand 1–5
Sandy loam/fine sand 1–3
Loam/ clay loam/clay well structured 0,5 – 2
Very fine sandy loam 0,2 – 0,5
Clay loam/clay, poorly structured 0,02 – 0,2
No biopores < 0,002
5. Transmisivitas (transmisivity, T)
Didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengalirkan air atau meneruskan
air per satuan lebar dari keseluruhan ketebalan akifer.
q k i D
Harga KD = transmisivitas = q/i
Contoh : tentukan transmisivitas suatu akifer dengan ketebalan 40 m bila k =
25 m/hari
T = k D = 25 40 = 1000 m3/hari
6. Infiltrasi dan perkolasi
Laju maksimum air yang dapat berinfiltrasi ke dalam tanah kering
berkurang, mulai dari harga tertinggi sampa ke harga terendah, dan
selanjutnya mencapat harga konstan ± 1 a’ 3 jam dari saat awal.
Harga yang mendekati harga konstan memberikan gambaran mengenai
geometri pori dalam top soil yang bervariasi dengan tekstur tanah dan sangat
dipengaruhi oleh struktur tanah.
Laju infiltrasi untuk beberapa jenis tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 1.2.Laju infiltrasi
Jenis tanah Total infiltrasi setelah Laju infiltrasi setelah
3 jam (mm) 3 jam (mm/jam)
Coarse textured soil 150 – 300 15 – 20
Medium textured soil 30 – 100 5 – 10
Fine textured soil 30 – 70 1–5
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-17
Tanah retak lebih banyak menyerap air (100-200 mm), tetapi retakan dapat
tertutup apabila terjadi runtuhan tanah. Pada laju infiltrasi akhir, kondisi sama
dengan k pada keadaan jenuh.
1.3. CONTOH SOAL
1) Diketahui curah hujan per tahun 1500 mm. Luas area 100 ha. Porositas 40%.
Kedalaman muka air tanah 2,0 m.
Estimasilah, berapa m3 air yang menjadi limpasan ?
Penyelesaian :
Volume hujan = 100 104 1500 10-3 = 1.500.000 m3
Volume yang meresap = 100 104 2 0,4 = 800.000 m3
Jadi yang menjadi limpasan = (1 – 8/15 ) 100 = 46,7%
2) Diketahui timbunan jalan di atas tanah gambut seperti pada gambar dibawah ini.
impervious
30 m
k = 20 mm/hari
1.2 m
tanah gambut 2m
impervious
Berapa debit rembesan per hari per km panjang jalan?
Penyelesaian :
Untuk panjang 1 km, penampang aliran = 1000 2 = 2000 m2
q = k I A = 20/1000 0,04 2000 = 1,6 m3/hari.
1.4. TERMINOLOGI
Subbab ini memuat istilah / terminologi yang berkaitan dengan pekerjaan drainase.
Aliran Permukaan (limpasan permukaan, surface runoff).
Lapisan air yang mengalir di permukaan tanah yang datangnya dari curah hujan.
Aliran Permanen ( Steady Flow )
Aliran dimana debit air yang mengalir pada saluran tidak berubah atau konstan
selama selang waktu tertentu
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-18
Aliran Tidak Permanen ( Unsteady Flow )
Aliran dimana debit air yang mengalir pada saluran berubah dalam selang waktu
tertentu.
Aliran Berubah ( Varied Flow )
Aliran pada saluran dimana kedalaman air berubah sepanjang saluran.
Aliran Seragam ( Uniform Flow )
Aliran pada saluran dimana kedalaman air tidak berubah sepanjang saluran.
Banjir ( Flood )
Kondisi debit pada saluran/sungai atau genangan pada lahan yang melebihi
kondisi normal yang umumnya terjadi. Kondisi normal diberi batas maksimum
sebagai kondisi yang tidak sampai mengganggu kegiatan dan merugikan
lingkungan.
Bantaran (Flood plain)
Bagian dari dataran banjir mulai dari tepi saluran atau sungai, sampai kaki
tanggul banjir. Bantaran termasuk bagian dari penampang saluran atau sungai
yang berfungsi menambah kapasitas saluran atau sungai untuk melewatkan debit
banjir yang lebih besar.
Badan Air ( Receiving water )
Tempat terakhir dimana saluran primer drainase bermuara. Dalam hal ini bisa
berupa sungai besar atau laut.
Berm (shoulder, bahu jalan)
Jalur tanah atau tanah ditanami rumput , yang dibuat dikiri kanan perkerasan
jalan, yang tidak boleh dilewati kendaraan.
Beronjong (gabion)
Susunan atau tumpukan batu kali atau batu pecah yang dipasang tanpa spesi
dengan cara memasukkannya didalam keranjang anyaman kawat baja.
Box Culvert
Gorong-gorong yang berpenampang melintang persegi. Biasanya dibuat dari
beton bertulang.
Busem (boezem, retarding basin, pond)
Kolam penampungan sementara limpasan banjir.
Daerah Pemukiman.
Kawasan yang diatasnya terdapat sejumlah perumahan yang dipakai sebagai
tempat tinggal.
Daerah Pematusan (drainage basin, catchment area)
Luasan daerah dimana curah hujan yang jatuh diatasnya , mengalir masuk ke
saluran atau sungai.
Dataran Banjir
Lahan ditepi kiri dan kanan saluran atau sungai yang akan tergenang pada
kondisi banjir.
Debit
Volume air yang melewati penampang saluran tiap detik.
Gorong-gorong
Bangunan bantu atau bangunan perlintasan yang berfungsi melintaskan air
melewati rintangan berupa jalan atau jalan kereta api.
Hidrograf
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-19
Grafik yang menggambarkan hubungan besarnya debit atau kedalaman air pada
sungai atau saluran, terhadap waktu.
Jagaan (wakking (Bld), freeboard)
Jarak vertical dari permuaan air sampai sisi atas tanggul atau tanah tepi saluran.
Limpasan
Aliran air pada alur saluran atau sungai yang datangnya berasal dari curah hujan
yang jatuh pada daerah pematusannya.
Plengsengan (Lining, revetment)
Perkuatan lereng saluran dari bahan penguat seperti aspal, pasangan batu, beton
atau beton bertulang.
Pemasukan tepi ( street inlet )
Lobang aliran yang dibuat pada dinding tepi berm atau diatas saluran tepi,
berfungsi melewatkan air dari limpasan pada permukaan jalan , masuk ke
saluran tepi.
Periode Ulang ( return periode )
Interval waktu rata-rata yang suatu peristiwa disamai atau dilampaui satu kali.
Sebagai contoh misalnya periode ulang 2 tahunan memberi arti bahwa
peristiwa tersebut akan disamai atau dilampaui sebanyak 2 kali dalam kurun
waktu 4 tahun, 3 kali dalam kurun waktu 6 tahun, 4 kali dalam kurun waktu 8
tahun, 10 kali dalam kurun waktu 20 tahun. Mengenai waktu kapan terjadinya
peristiwa tadi disamai atau dilampaui , tidak ( bisa ) ditentukan atau dipastikan.
Plengsengan ( revetment )
Lining yang dibuat dari bahan pasangan batu.
Saluran terbuka ( open channel )
Saluran yang mempunyai permukaan air bebas atau yang permukaan airnya
berhubungan dengan atmosfir.
Saluran Drainase Kota
Saluran drainase yang menerima dan membuang air dari daerah pemukiman atau
dari daerah perkotaan ke badan air, dengan segala fasilitas drainase yang
diperlukan.
Saluran Drainase Basin
Saluran drainase yang menerima air dari luar daerah pemukiman dan
membuang air ke badan air melewati perkotaan.
Sistem Drainase
Kumpulan saluran yang membentuk struktur jaringan saluran mulai dari saluran
primer sampai saluran tepi dengan segala bangunan bantu yang ada didalam
daerah pematusannya termasuk badan air dimana saluran primernya bermuara.
Saluran Tepi (side ditch)
Saluran tepi jalan yang berfungsi menerima air pematusan dari permukaan jalan
dan lahan yang berada berseberangan dengan jalan.
Saluran Kwarter
Saluran yang menerima dan menyalurkan limpasan dari saluran tepi dan air
pematusan dari lahan yang terletak di kiri kanan saluran. Luas daerah pematusan
saluran kwarter, maksimum 5 ha untuk daerah datar dan 10 ha untuk daerah
miring.
Saluran Tersier
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-20
Saluran yang menerima dan menyalurkan limpasan dari saluran kwarter dan air
pematusan dari lahan yang terletak di kiri kanan saluran . Hulu saluran tersier
berawal dari pertemuan dua saluran kwarter.Luas daerah pematusan untuk
saluran tersier adalah maksimum10 ha untuk daerah datar dan maksimum 20 ha
untuk daerah miring.
Saluran Sekunder
Saluran drainase yang berawal dari pertemuan dua saluran tersier , menerima
dan menyalurkan air yang masuk dari saluran tersier, saluran kwarter, saluran
tepi danlahan yang berada ditepi saluran bersangkuta.Luas daerah pematusan
untuk saluran sekunder adalah 20 ha untuk daerah datar , dan 40 ha untuk daerah
miring.
Saluran Primer
Saluran primer berawal dari pertemuan dua saluran sekunder, menerima air
pematusan dari saluran sekunder, saluran tersier, saluran kwarter dan saluran
tepi serta lahan yang berada di kiri kanan saluran.
Saluran Prismatis.
Saluran prismatis adalah saluran yang mempunyai bentuk dan dimensi sama
sepanjang saluran.
Trotoar.
Jalur tanah atau perkerasan yang dibuat dikiri kanan jalan, yang diperuntukkan
bagi pejalan kaki dan tidak boleh dilewati kendaraan.
Waktu Konsentrasi
Waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan partikel air dari titik terjauh sampai
kesuatutempat yang dimaksud dengan Titik Kontrol.
1.5. RANGKUMAN
Ada dua macam drainase, yaitu drainase basin dan drainase perkotaan/
permukiman.
Drainase basin berkaitan dengan pengaturan/pengendalian sungai, sedang
drainase perkotaan / permukiman berkaitan dengan pengaturan serta
pembuangan air hujan dan air buangan domestik serta air tanah.
Pada kondisi tertentu, alur sungai tidak mampu melewatkan suatu debit,
sehingga terjadilah banjir yang dinamakan banjir makro.
Pada kondisi saluran tidak mampu melewatkan limpasan hujan, terjadilah banjir
yang dinamakan banjir mikro.
Apabila tidak diatur pembuangannya, air limbah dan air berlebih dapat
membahayakan kesehatan lingkungan.
Perencanaan saluran drainase mempertimbangkan komponen alam, yaitu tanah
dan air tanah, topografi daerah dan curah hujan.
Drainase PS 1379 – 2006
Modul 1-21
Air tanah tidak bisa diabaikan kalau permukaan air tanahnya relatif tinggi
(dangkal).
1.6. SOAL LATIHAN
Diskusikanlah soal berikut :
1. Beri contoh masalah drainase basin, jelaskan menurut pengetahuan anda tentang
penyebab banjir.
2. Beri contoh masalah drainase perkotaan, jelaskan menurut pengetahuan anda dan
tentang penyebabnya.
3. Jelaskan hubungan antara muka air tanah yang dangkal di Surabaya Timur dengan
masalah drainase di wilayah tersebut.
4. Sebutkan keuntungan dan kerugian sistem saluran terpisah dan tercampur.
1.7. Daftar pustaka
Masduki, Drainase Perkotaan, Diktat Kuliah Institut Teknologi Bandung, 1990
Drainase PS 1379 – 2006
Anda mungkin juga menyukai
- Waterproofing Kelompok 4Dokumen7 halamanWaterproofing Kelompok 4Aditya NurBelum ada peringkat
- UPDATE - Surat Tugas KBK Dan Lampiran Agustus 2020 - Mei 2021Dokumen7 halamanUPDATE - Surat Tugas KBK Dan Lampiran Agustus 2020 - Mei 2021David FajarBelum ada peringkat
- Capping Beam Kelompok 4Dokumen9 halamanCapping Beam Kelompok 4Aditya NurBelum ada peringkat
- 6953 20175 1 PBDokumen6 halaman6953 20175 1 PBAditya NurBelum ada peringkat
- Aldo Kurniawan - 180523630052 - Gagasan Inovasi Kayu Tak TerpakaiDokumen3 halamanAldo Kurniawan - 180523630052 - Gagasan Inovasi Kayu Tak TerpakaiAditya NurBelum ada peringkat
- OneWay-2020Dokumen16 halamanOneWay-2020Aditya NurBelum ada peringkat
- Nilai Dan KelompokDokumen2 halamanNilai Dan KelompokAditya NurBelum ada peringkat