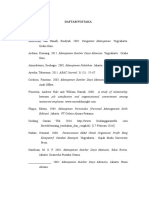Ilmu Dan Filsafat Satu
Ilmu Dan Filsafat Satu
Diunggah oleh
Iand Graha SaputraHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Ilmu Dan Filsafat Satu
Ilmu Dan Filsafat Satu
Diunggah oleh
Iand Graha SaputraHak Cipta:
Format Tersedia
Dr. Djoko Poernomo, M.
Si
Dosen Mata Kuliah Filsafat Ilmu
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
5 September 2014 (1)
Alkisah bertanya seorang awam ke filsuf,
Sebutkan berapa jenis manusia berdasarkan
pengetahuannya. Filsuf berpantun:
Ada orang yang tahu di tahunya
Ada orang yang tahu di tidaktahunya
Ada orang yang tidak tahu di tahunya
Ada orang yang tidak tahu di tidaktahunya
Bagaimana caranya agar saya orang awam
mendapatkan pengetahuan yang benar?
Filsuf: ketahuilah apa yang kau tahu dan
ketahuilah apa yang kau tidak tahu.
Pengetahuan dimulai dengan rasa INGIN TAHU,
kepastian dimulai dengan rasa RAGU-RAGU, dan
filsafat dimulai dengan keduanya.
Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang
telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu.
Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak
semuanya akan pernah kita ketahui dalam
kesemestaan yang seakan tidak terbatas ini.
Berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam
keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh
sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita
jangkau.
Ilmu merupakan pengetahuan yang kita gumuli sejak
bangku sekolah dasar sampai sekarang.
Berfilsafat tentang ilmu berarti kita berterus terang
kepada diri sendiri:
1) Apakah sebenarnya yang kita ketahui tentang
ilmu?
2) Apakah ciri-ciri yang hakiki yang membedakan ilmu
dari pengetahuan lainnya yang bukan ilmu?
3) Bagaimana kita ketahui bahwa ilmu merupakan
pengetahuan yang benar?
4) Kriteria apa yang kita pakai dalam menentukan
kebenaran ilmiah?
5) Mengapa kita mesti mempelajari ilmu? Apakah
kegunaan yang sebenarnya?
Berfilsafat berarti berendah hati
mengevaluasi segenap pengetahuan yang
telah kita ketahui:
1) Apakah ilmu telah mencakup segenap
pengetahuan yang seyogyanya kita ketahui
dalam kehidupan ini?
2) Dibatas manakah ilmu mulai dan di batas
manakah ia berhenti?
3) Kemanakah kita harus berpaling di batas
ketidaktahuan ini?
4) Apakah kelebihan dan kekurangan ilmu?
Seorang yang berfilsafat dapat diumpamakan
berpijak di bumi sedang tengadah ke langit.
Ia ingin mengetahui hakekat dirinya dalam
kesemestaan. maknanya.
Karakteristik (sifat) berpikir filsafat adalah:
1) Menyeluruh
2) Mendalam
3) Spekulatif
Seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal
ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri.
Ia ingin melihat hakekat ilmu dalam
konstelasi pengetahuan lainnya. Ia ingin
tahu kaitan ilmu dengan moral, kaitan ilmu
dengan agama. Ia ingin yakin apakah ilmu itu
membawa kebahagiaan kepada dirinya.
Simpul SOCRATES: Yang saya tahu, saya
tidak tahu apa-apa. Sungguh! Betapa rendah
hati ia.
Seorang yang berpikir filsafati tidak lagi percaya
begitu saja bahwa ilmu itu benar.
1) Mengapa ilmu dapat disebut benar?
2) Bagaimana proses penilaian berdasarkan
kriteria tersebut dilakukan?
3) Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu benar
sendiri itu apa?
Bagaikan sebuah lingkaran, kita harus mengurai
mulai dari satu titik awal dan akhir. Bagaimana
menentukan titik awal (atau akhir) yang benar?
Memang tidak mudah menjangkau semuanya.
kitaberspekulasi
SHAKESPEARE: Masih banyak lagi di langit dan di
bumi selain yang terjaring dalam filsafatmu.
Kita mulai curiga terhadap filsafat: bukankah
spekulasi adalah suatu dasar yang tidak bisa
diadakan?
Jawab filsuf: memang, namun itu tidak bisa
dihindarkan. Bagai menyusur sebuah lingkaran, kita
harus menentukan sebuah titik awal bagaimanapun
spekulatifnya. Yang penting adalah dalam prosesnya,
baik dalam analisis maupun pembuktiannya, kita bisa
memisahkan spekulasi mana yang dapat diandalkan
dan mana yang tidak.
Tugas utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar
yang dapat diandalkan. Apakah yang disebut logis?
Apakah yang disebut benar? Apakah yang disebut
sahih? Apakah alam ini teratur atau kacau? Apakah
hidup ini ada tujuannya atau absurd? Adakah hukum
yang mengatur alam dan segenap sarwa kehidupan?
Kita sebaiknya menyadari bahwa semua
pengetahuan yang sekarang ada dimulai dengan
spekulasi. Dari serangkaian spekulasi, kita dapat
memilih buah pikiran yang dapat diandalkan yang
merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan.
Tanpa menetapkan kriteria tentang apa yang
disebut benar maka tidak mungkin pengetahuan
lain berkembang di atas dasar kebenaran.
Tanpa menetapkan apa yang disebut baik atau
buruk maka kita tidak mungkin berbicara
tentang moral.
Tanpa wawasan apa yang disebut indah atau
jelek tidak mungkin kita berbicara tentang
kesenian.
Filsafat bagaikan pasukan marinir yang merebut
pantai untuk pendaratan pasukan infantri.
Pasukan infantri adalah sebagai pengetahuan
yang diantaranya adalah ILMU.
Filsafatlah yang memenangkan tempat berpijak
bagi kegiatan keilmuan. Setelah itu ilmulah yang
membelah gunung dan merambah hutan,
menyempurnakan kemenangan ini menjadi
pengetahuan yang dapat diandalkan.
Setelah penyerahan dilakukan maka filsafat pun
pergi. Ia kembali menjelajah laut lepas:
berspekulasi dan meneratas.
Semua ilmu, baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-
ilmu sosial, bertolak dari pengembangannya
bermula sebagai filsafat.
Issac Newton (1642-1627) menulis hukum-hukum
fisikanya sebagai Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica (1686), Adam Smith
(1723-1790) bapak ilmu ekonomi menulis buku
The Wealth of Nations (1776) dalam fungsinya
sebagai Professor of Moral Philosophy di
Universitas Glasgow.
Nama asal fisika adalah filsafat alam (natural
philosophy) dan nama asal ekonomi adalah
filsafat moral (moral philosophy).
Terdapat taraf peralihan. Dalam taraf ini, bidang filsafat
menjadi lebih sempit, tidak lagi menyeluruh melainkan
sektoral, misalnya ilmu ekonomi.
Peralihan awal konseptual ilmu masih mendasarkan
kepada norma-norma filsafat. Misalnya ekonomi masih
merupakan penerapan etika dalam kegiatan manusia
memenuhi kebutuhan hidupnya. Metode yang dipakai
adalah normatif (yang seharusnya) dan deduktif
berdasarkan asas-asas moral yang filsafati.
Tahap selanjutnya ilmu menyatakan dirinya otonom dari
konsep-konsep filsafat dan mendasarkan sepenuhnya
kepada (penemuan) hakekat alam sebagaimana adanya.
Dalam menyusun pengetahuan tentang alam dan isinya ini
maka manusia tidak lagi mempergunakan metode yang
bersifat normatif dan deduktif melainkan kombinasi antara
deduktif dan induktif dengan jembatan yang berupa
pengajuan hipotesis yang dikenal sebagai metode logico-
hypothetico-verifikatif.
Tiap ilmu dimulai dengan filsafat dan diakhiri dengan
seni muncul dalam hipotesis dan berkembang ke
keberhasilan ujar Will Durant (1933). AUGUSTE COMTE
(1798-1857) membagi 3 tingkatan perkembangan
pengetahuan tersebut ke dalam tahap: religius, metafisik,
dan positif.
Tahap pertama, asas religilah yang dijadikan postulat
ilmiah sehingga ilmu merupakan deduksi atau penjabaran
dari ajaran religi.
Tahap berikutnya, orang mulai berspekulasi tentang
metafisika (keberadaan) ujud yang menjadi obyek
penelaahan yang terbebas dari dogma religi dan
mengembangkan sistem pengetahuan di atas dasar postulat
metafisik tersebut.
Tahap terakhir, adalah tahap pengetahuan ilmiah, (ilmu)
dimana asas-asas yang dipergunakan diuji secara positif
dalam proses verifikatif yang obyektif.
Selaras dengan sifatnya, maka filsafat
menelaah SEGALA masalah yang mungkin
dapat dipikirkan oleh manusia. Sesuai dengan
fungsinya sebagai PIONIR, ia mempersoalkan
hal-hal yang pokok: terjawab masalah satu,
ia pun merambah pertanyaan lain, begitu
seterusnya sesuai dengan jamannya.
Ilustrasi permasalahan yang dikaji filsafat:
What is a man?
What is?
What?
Pada tahap awal sekali, filsafat mempersoalkan
siapakah manusia itu. HALO SIAPA KAU?
Contoh manusia dalam perspektif ilmu ekonomi
dan ilmu administrasi. Ilmu ekonomi mempunyai
asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang
bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya
dan menjauhi ketidaknyamanan semungkin bisa.
Ia bisa serakah, hedonis, dsb (homo
economicus). Ilmu Administrasi mempunyai
tujuan menelaah kerjasama antar manusia dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
The righ (assumption of) man on the right place
penting banget.
Pertanyaan berkisar tentang hidup dan
eksistensi manusia.
Apakah hidup ini sebenarnya?
Apakah hidup ini absurd, tanpa arah, tanpa
bentuk, bagaikan amuba yang berzigzag?
Ini berhubungan dengan epistemologi (dan bahasa).
Ilustrasi: biarpun seorang ilmuwan terkemuka dalam
karya ilmiahnya mengutip sejumlah ilmuwan dunia
bahkan pemenang hadiah Nobel, mengemukakan
sejumlah fakta yang aktual, namun bila tidak jelas
yang mana masalah, yang mana hipotesis, yang mana
kerangka pemikiran, yang mana kesimpulan, yang
keseluruhannya terkait dan tersusun dalam penalaran
ilmiah, maka itu percuma saja (GIGO = garbage in
garbage out).
WITTGENSTEIN (1972): tugas utama filsafat bukanlah
menghasilkan sesusun pernyataan filsafati melainkan
menyatakan sebuah pernyataan sejelas mungkin.
Ilustrasi: Masalah utama disertasi saudara, ialah
saudara berlaku sebagai seorang pemborong
bahan bangunan dan bukan arsitek yang
membangun rumah. Memang banyak sekali,
bertumpuk di sana sini, namun tidak merupakan
dinding; kayunya menumpuk sekian meter kubik
namun tidak merupakan atap. Sebagai ilmuwan
saudara harus membangun kerangka dengan
bahan-bahan tersebut, kerangka pemikiran yang
orisinal dan meyakinkan, disemen oleh penalaran
dan pembuktian yang tidak meragukan kata
seorang penguji.
Ah daripada disebut pemborong bahan
bangunan, belajar lagi sajalah
Epistemologi (Filsafat Pengetahuan)
Etika (Filsafat Moral)
Estetika (Filsafat Seni)
Metafisika
Politik (Filsafat Pemerintahan)
Filsafat Agama
Filsafat Ilmu
Filsafat Pendidikan
Filsafat Hukum
Filsafat Sejarah
Filsafat Matematika, dll.
Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi
(filsafat pengetahuan) yang secara spesifik
mengkaji hakekat ilmu (pengetahuan ilmiah).
Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang
mempunyai ciri-ciri tertentu. Meskipun secara
metodologis ilmu tidak membedakan antara
ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial, namun
karena permasalahan-permasalahan teknis yang
bersifat khas, maka filsafat ilmu ini sering dibagi
menjadi filsafat ilmu-ilmu alam dan filsafat ilmu-
ilmu sosial.
Namun tidak terdapat perbedaan yang prinsipil
antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial,
dimana keduanya mempunyai ciri-ciri keilmuan
yang sama.
Filsafat ilmu merupakan telaahan secara
filsafat yang ingin menjawab beberapa
pertanyaan mengenai hakekat ilmu seperti
yang terkait dengan:
1) Landasan ontologis
2) Landasan epistemologis
3) Landasan aksiologis
Obyek apa yang ditelaah ilmu?
Bagaimana ujud yang hakiki dari obyek
tersebut?
Bagaimana hubungan antara obyek tadi
dengan daya tangkap manusia (seperti
berpikir, merasa dan mengindera) yang
membuahkan pengetahuan?
Bagaimana proses yang memungkinkan
ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu?
Bagaimana prosedurnya?
Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita
mendapatkan pengetahuan yang benar?
Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apa
kriterianya?
Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita
dalam mendapatkan pengetahuan yang
berupa ilmu?
Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu
dipergunakan?
Bagaimana kaitan antara cara penggunaan
tersebut dengan kaidah-kaidah moral?
Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah
berdasarkan pilihan-pilihan moral?
Bagaimana kaitan antara teknik prosedural
yang merupakan operasionalisasi metode
ilmiah dengan norma-norma
moral/profesional?
Anda mungkin juga menyukai
- Artikelpengaruh Lingkungan Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Cuci Sarang Burung Walet Mangli JayaDokumen16 halamanArtikelpengaruh Lingkungan Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Cuci Sarang Burung Walet Mangli JayaIand Graha SaputraBelum ada peringkat
- Daftar Pustaka AgustDokumen5 halamanDaftar Pustaka AgustIand Graha SaputraBelum ada peringkat
- Daftar PustakaDokumen2 halamanDaftar PustakaIand Graha SaputraBelum ada peringkat
- Artikelpengaruh Lingkungan Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Cuci Sarang Burung Walet Mangli JayaDokumen16 halamanArtikelpengaruh Lingkungan Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Cuci Sarang Burung Walet Mangli JayaIand Graha SaputraBelum ada peringkat
- Budaya Administrasi - Purno WinardiDokumen11 halamanBudaya Administrasi - Purno WinardiIand Graha Saputra100% (1)
- Hubungan Antara Kehormatan, Etika Dan Akuntabilitas SeorangDokumen8 halamanHubungan Antara Kehormatan, Etika Dan Akuntabilitas SeorangIand Graha SaputraBelum ada peringkat
- Strategi Pemberdayaan UMKMDokumen32 halamanStrategi Pemberdayaan UMKMIand Graha SaputraBelum ada peringkat
- EPISTEMOLOGIDokumen20 halamanEPISTEMOLOGIIand Graha SaputraBelum ada peringkat
- Interaksi InternalDokumen8 halamanInteraksi InternalIand Graha SaputraBelum ada peringkat
- Filsafat Ilmu AdministrasiDokumen17 halamanFilsafat Ilmu AdministrasiIand Graha SaputraBelum ada peringkat
- Pengantar Kuliah Bahasa Indonesia KomunikasiDokumen21 halamanPengantar Kuliah Bahasa Indonesia KomunikasiIand Graha SaputraBelum ada peringkat
- Budidaya Jamur Tiram Putih Yang Bernama Latin Pleurotus Ostreatus Ini Masih Tergolong BaruDokumen7 halamanBudidaya Jamur Tiram Putih Yang Bernama Latin Pleurotus Ostreatus Ini Masih Tergolong BaruIand Graha SaputraBelum ada peringkat
- Tantangan Dan Masa Depan IlmuanDokumen11 halamanTantangan Dan Masa Depan IlmuanIand Graha SaputraBelum ada peringkat