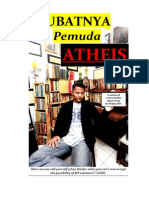Di Rantau
Diunggah oleh
Wahyu Budi NugrohoHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Di Rantau
Diunggah oleh
Wahyu Budi NugrohoHak Cipta:
Format Tersedia
1
Di Rantau
Wahyu BN
But, I dont want comfort. I want God. I want poetry.
I want danger. I want freedom. I want goodness. I want sin.
[Aldous Huxley, Brave New World]
Denpasar. Aku di sini.
Tiga-empat hari awal adalah rentang terberat. Aku rindu kampung
halaman, rinduuu sangaaat. Jogja, tempat dimana keamanan dan
kenyamanan jadi jaminan bagi tiap mereka yang menetapinya. But, aku
tahu, yang terberat bukan itu, melainkan kamar sekaligus perpus pribadiku.
Ruang dimana produktivitasku tergenjot hingga ke batas, dan kini, aku
tercerabut darinya; bak hiu yang terdampar di pesisir Sanur. Lemas.
Lebih lemas. Itulah yang kurasa kala menyaksikan kamar kosku
untuk pertama kalinya. Entah sudah berapa lama kamar ini tak bertuan,
kata Bu Katni sih, pembantu di rumah itu, tak lebih dari sebulan. Lantainya
kotor, sangat kotor. Hampir dua hari kukenakan sandal di dalamnya.
Maklum, aku belum punya perangkat bersih-bersih, sebetulnya bukan itu
juga yang jadi soal, meski Bu Katni mengatakan aku bisa meminjam sapu
dan pel darinya, tapi aku masih malas; baru saja kutempuh perjalanan
panjang, serasa ingin berebah untuk dua-tiga hari ke depan.
Nyatanya, yang terparah bukan itu. Kamar mandi tak berlampu,
1
lantainya juga kotor, remah kayu tampak sering di permukaan, tak butuh
waktu lama tuk memergoki biangnya: satu sudut plafon yang jebol. Sejurus,
Bu Katni berucap, Itu bak mandinya barusan saya kuras, Mas. Mungkin,
itu diucapnya tuk meyakinkanku bila kamar kos ini masih terjamah (baca:
1
Kamar kos dengan kamar mandi dalam.
Caution!
PRIVATE
not [yet] for
wide publication
2
terawat), pun tuk meredam gesturku yang tak antusias pasca
menyaksikannya.
Well, apa boleh buat, 1 Mei 2014, kurang-lebih pukul 16.00; itulah kali
pertama kuinjakkan kaki di Denpasar. Aku tak ingin merepotkan siapa pun,
terlebih menginap di kos Mr. Idin, dosen HI yang dirujuk Mrs. Ikma tuk
membantuku setibanya di tanah ini, tanah para dewa. Yep, langsung
kuambil kamar kos itu.
Sebagai eksisten-SIAL-is tulen, segera kulancarkan pemaknaan dan
manipulasi atas ruangan ini. Tak ada yang sempurna: Tak ada akar, Ram
Punjabi. Hmm, ya, ya; ini tak buruk-buruk amat, setidaknya mirip kamarku
di Jogja, selain daun pintu masuk dan pintu kamar mandi, kamar ini
memiliki satu daun pintu lagi: menuju balkon!
Tapi, balkon bukanlah pelipurku, tentu kamar balkon kos ini jauh
ketimbang Caf Bon Viveur
2
. Daun pintu masuk dan pintu menuju balkon
yang nyaris saling berhadapan lah yang memekarkan hatiku. Sebagai
perokok, aku sarat memperhatikan sirkulasi udara. Di Jogja saja,
kudayagunakan dua kamar; satu kamar untuk membaca dan menulis
sembari merokok sepagi hingga malam hari, dan satu lagi kamar untuk
tidur sedari pagi hingga pagi.
Berbekal ucap Bu Katni barusanbak mandi yang baru saja
dikurassegera kubuka keran; ught, besar hasratku tuk mandi besar! Andai
kufoto sapu tangan penyeka wajah waktu itu sebagai bukti: hitam timbal
asap.
Kamar mandi tak berlampu. Kuandalkan pancaran lampu kamar.
Yep, kubiarkan pintu kamar mandi terbuka, aku mandi dalam remang-
remang. Dan, keesokan paginya, kutuai tiga guratan herpes di pergelangan
tangan kanan. Apa? Barusan dikuras? Hah?! *&^%$#@!
Perih. Perih sekali.
2
Julukanku dan teman-teman dekat untuk balkon kamar di Jogja.
3
Makan dan minum. Tak ada rice cooker, tak ada dispenser; alhasil,
aku harus selalu keluar tuk memenuhi sepasang kebutuhan itu. Nasi ayam
plus air putih: Rp 12.000,-. Wow! Di Jogja bisa cuma lima-enam ribu, shock.
Minumku; air putih botol, teh botol, kopi botol; stresss.
Tak tertahankan lagi, malam hari ketiga kubeli dispenser dan galon
air. Temanku dari Medan, Togaranta Ginting, yang kebetulan kala itu
bermalam di kos, membantuku dalam operasi ini. Dan, ketika esok paginya
kubuat kopi panasku sendiri: Aw aw aw! Aku serasa berada di SURGA!
Semuanya menjadi kian enteng.
Hari kelima, kubeli rice cooker. Namun, tabung ceper ajaib ini baru
terpakai dua hari kemudian. Aku sarat membeli beras dan piring terlebih
dahulu, jadilah kusambangi Pasar Sanglah. Emm, sebetulnya, sudah dua-
tiga kali kubelanja di sinimembeli taplak meja, keset, pisau, handuk, etc.
Sejak awal, telah kupilih toko kelontong favoritku. Kenapa favorit? Apalagi
kalau bukan karena anak perempuan ibu pedagang yang cantik uhuy-uhuy.
Toko kelontong ini dimiliki perantauan Sunda, anak perempuan ibu
pedagang, yang kemudian kutahu bernama Lia, membantu ibunya di sela
kesibukan kuliah. Wajahnya oval-putih-bersih dengan mata tajam tak
mengancam, yang terbaik dari semua itu: mahkotanya berbalut hijab besar
bak ukhti-ukhti di kota Jogja. Duh, Gusti! Betapa terbatasnya menemukan
jodoh seiman di sini, dan kini Kau tunjukkan padaku wanita cantik berhijab
syari! Duh duh duh, puyeng kepalaku
Tak mau kehilangan momen, kuajak Lia sesekali bercakap saat
mengambil barang-barang yang kubutuhkan. Rupanya, ia kuliah di salah
satu akademi ilmu komputer dan informatika kota ini.
Wah, berarti pinter komputer dong? lancarku padanya.
Ah, nggak juga Lia menjawab dengan senyum malu-malu,
kemudian ia menundukkan kepalanya.
Aku pun melanjutkan, Facebook, Twitter
Ia kembali menatapku, kali ini dengan senyum yang lebih rekah,
seketika, ia kembali menundukkan kepala. Duh, Gusti co cweet!
4
Oke, cukup tentang Lia.
Aku mulai memasak nasi, dengan begitu, cukup kubeli lauk-pauk di
luar. Nyatanya, keterkejutanku masih berlanjut. Ayam goreng: Rp 8.000,-;
lele goreng: Rp 8.000,-. Baru kali ini kutemukan di negeri Endoneysa ini,
ayam goreng dan lele goreng ada di kasta yang sama! What the Beruntung,
negara memberi jatah makan Rp 20.000,- per hari, tak besar memang.
Yang terparah; hingga kini belum kucuci pakaianku sendiri, masih
kuandalkan Sinchan Laundry. Maklum, sedari TK hingga S2 aku tak pernah
mencuci dan menseterikaserius. Setidaknya, aku telah berniat membuka
Google tuk mencari tahu ihwal mencuci pakaian yang baik dan benar, juga
menseterika.
Aku tak mau ditindak dunia.
Aku ingin menindaknya.
Tahap demi tahap.
Brave-New-World. Hehe
Denpasar, 16 Mei 2014.
Anda mungkin juga menyukai
- Andy Warhol Dan Eksentrisme Budaya PopDokumen5 halamanAndy Warhol Dan Eksentrisme Budaya PopWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat
- TAUBATNYA Pemuda ATHEISDokumen5 halamanTAUBATNYA Pemuda ATHEISWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat
- Mengeja Eksistensialisme Emmanuel LevinasDokumen7 halamanMengeja Eksistensialisme Emmanuel LevinasWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat
- "Kosong!" by Wahyu BNDokumen157 halaman"Kosong!" by Wahyu BNWahyu Budi Nugroho100% (1)
- SiluetDokumen38 halamanSiluetWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat
- 'Mitosifikasi Kejawen' Sebagai Strategi Alternatif Pengembangan Pariwisata DIY Bagi Turis MancanegaraDokumen14 halaman'Mitosifikasi Kejawen' Sebagai Strategi Alternatif Pengembangan Pariwisata DIY Bagi Turis MancanegaraWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat
- 'Alayers', Generasi Progresif Dan RevolusionerDokumen8 halaman'Alayers', Generasi Progresif Dan RevolusionerWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat
- Mr. Bean & EksistensialismeDokumen3 halamanMr. Bean & EksistensialismeWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat
- KatarsisDokumen6 halamanKatarsisWahyu Budi Nugroho0% (1)
- 'Occupy Wall Street' Dan Penguatan Gerakan Sosial BaruDokumen10 halaman'Occupy Wall Street' Dan Penguatan Gerakan Sosial BaruWahyu Budi Nugroho100% (1)
- Pemuda, Bunuh Diri Dan ResiliensiDokumen24 halamanPemuda, Bunuh Diri Dan ResiliensiWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat
- Eksistensialisme Vs Frankfurt SchoolDokumen10 halamanEksistensialisme Vs Frankfurt SchoolWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat
- Kapitalisme Global, Labelisasi Halal Dan Fenomena GlokalisasiDokumen8 halamanKapitalisme Global, Labelisasi Halal Dan Fenomena GlokalisasiWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat
- Pancasila Sebagai Pseudo IdeologiDokumen7 halamanPancasila Sebagai Pseudo IdeologiWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat
- Fenomenologi Eksistensial Sebagai Instrumen Pereduksi Radikalisme BeragamaDokumen13 halamanFenomenologi Eksistensial Sebagai Instrumen Pereduksi Radikalisme BeragamaWahyu Budi NugrohoBelum ada peringkat