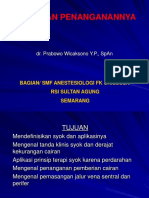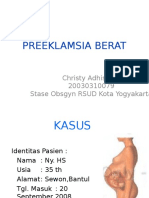2.1. Definisi Penyakit Ginjal Kronik: Cast (Hipertensi Tidak Termasuk)
2.1. Definisi Penyakit Ginjal Kronik: Cast (Hipertensi Tidak Termasuk)
Diunggah oleh
eloooyiy0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
7 tayangan18 halamanJudul Asli
CKD.docx
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
7 tayangan18 halaman2.1. Definisi Penyakit Ginjal Kronik: Cast (Hipertensi Tidak Termasuk)
2.1. Definisi Penyakit Ginjal Kronik: Cast (Hipertensi Tidak Termasuk)
Diunggah oleh
eloooyiyHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 18
2.1.
Definisi Penyakit Ginjal Kronik
Penyakit ginjal kronik adalah adalah suatu keadaan klinis yang ditandai
dengan penurunan fungsi ginjal yang ireversibel, pada suatu derajat yang memerlukan
terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa dialisis atau transplantasi ginjal. Kriteria
definisi CKD:
1. Kerusakan ginjal yang terjadi lebih dari 3 bulan, berupa kelainan struktural
atau fungsional dengan atau tanpa laju filtrasi glomerulus dengan manifestasi
kelainan patologis (yang ditentukan secara radiologik misalnya, terdapatnya
kista, massa, scarring, atropi ginjal; yang ditentukan secara histologik,
misalnya kelainan pada hasil biopasi ginjal) atau ditemukannya marker
kerusakan ginjal seperti mikroalbuminuria, proteinuria, hematuria,
cast(hipertensi tidak termasuk).
2. GFR kurang dari 60 ml/menit/1,73 m2 selama 3 bulan dengan atau tanpa
kerusakan ginjal (Suwitra, 2006).
2.2. Epidemiologi Penyakit Ginjal Kronik
Data dan studi epidemiologi tentang penyakit ginjal kronik di Indonesia
dapat dikatakan tidak ada. Yang adapun juga langka adalah studi atau data
epidemiologi klinik. Pada saat ini tidak dapat dikemukakan pola prevalensi di
Indonesia, demikian pula morbiditas dan mortalitas. Data klinik yang ada berasal dari
RS Referal Nasional, RS Referal Provinsi, RS Referal Swasta Spesialitik. Dengan
demikian dapat dimengerti bahwa data tersebut berasal dari kelompok yang khusus
(Perkovic, 2004)
Kesulitan dalam menentukan angka yang tepat tentang prevalensi penyakit
ginjal kronik di Indonesia adalah karena banyaknya pasien yang datang ke rumah
sakit dalam stadium terminal atau karena memerlukan dialisis. Namun di Amerika
Serikat diperkirakan sekitar 6%dari populasi dewasa menderita gagal ginjal kronik
dengan GFR > 60 mL/min per 1.73m2 (stadium 1 dan 2 ) dan 4.5% berada dalam
stadium 3 dan 4 (Santoso, 2003).
2.3. Etiologi dan Patofisiologi Penyakit Ginjal Kronik
Tabel 2.1. Penyebab utama Penyakit Ginjal Kronik (Perkovic, 2004)
Penyebab Contoh
Glomerulopati (primer) Fokal glomerulosklerosis
Nefropati IgA
Membranoproliferatif gromerulonefritis
Nefropati membranosa
Glomerulopati terkait penyakit sistemik Amiloidosis
dan sekunder Hepatitis B dan C
Infeksi
DM
HUS
SLE
RA
Sindroma Goodpasture
Glomerulonephritis post-infeksi
Wegener’s granulomatosis
Nefropati herediter Nefritis herediter (sindroma Alport’s)
Penyakit kistik
Penyakit ginjal polikistik
Hipertensi Glomerulosklerosis malignan
Nefroangiosklerosis
Uropati Obstruktif BPH
Fibrosis retroperitoneal
Obstruksi ureter (kongenital, kalkulus,
keganasan)
Refluks vesikoureter
Penyakit makrovaskular ginjal Stenosis arteri renal (aterosklerosis atau
dysplasia fibromuskular)
Ateroemboli
Trombosis vena renalis
Patofisiologi penyakit ginjal kronik melibatkan dua mekanisme: (1) Adanya
mekanisme spesifik (contohnya kompleks imun dan mediator inflamasi pada beberapa
tipe glomerulonephritis atau paparan toksin pada penyakit tertentu) dan (2)
mekanisme progresif berupa hiperfiltrasi dan hipertrofi nefron yang masih berfungsi.
Hipertensi sistemik yang terjadi mengakibatkan hipertensi glomerulus. Ginjal
secara normal dilindungi dari hipertensi sistemik dengan adanya mekanisme
otoregulasi. Namun, hal ini tidak terjadi pada tekanan darah yang tinggi. Hipertensi
glomerulus yang terjadi memicu perubahan lokal pada hemodinamik glomerulus
sehingga terjadi kerusakan glomerulus. Respon dari pengurangan jumlah nefron
diperantarai oleh hormon vasoaktif, sitokin, dan faktor pertumbuhan.
Hipertensi glomerulus normalnya merupakan mekanisme adaptasi nefron yang
tersisa untuk meningkatkan kerja glomerulus akibat kehilangan nefron. Dengan
adanya mekanisme adaptasi ini, kehilangan 75% jaringan renal hanya mengakibatkan
turunnya GFR 50% dari normal (Perkovic, 2004). Hal ini berarti hipertensi sistemik
ditranslasikan secara langsung pada barrier filtrasi glomerulus yang menyebabkan
kerusakan glomerulus. Namun, pada saat ini, terjadi hipertrofi dan hiperfiltrasi renal
yang mengakibatkan jaringan renal lebih terkekspos dengan jumlah zat berbahaya
yang lebih banyak (Matovinovic, 2001).
Hipertensi kronik bahkan menyebabkan vasokonstriksi dan sklerosis arteriol
yang menyebabkan atrofi glomerulus dan tubulointerstitial. Faktor pertumbuhan
lainnya seperti angiotensin II, EGF, PDGF, TGF-β, aktivasi kanal ion dan respon gen
awal tertentu terlibat dalam hubungan tekanan darah yang tinggi yang menyebabkan
proliferasi miointima dan sklerosis pembuluh darah (Matovinovic, 2001).
Peningkatan aktivitas RAA yang terjadi juga dapat mengakibatkan hipertrofi dan
sklerosis pada nefron yang masih aktif. Sklerosis yang terjadi disebabkan TGF-β.
TGF-β dan faktor pertumbuhan lainnya penting untuk fibrogenesis glomerulus.
Sitokin ini menstimulasi sel glomerulus untuk memproduksi ECM, menghambat
sintesa protease (Matovinovic, 2001).
Diagnosis Penyakit Ginjal Kronik
Ketika pasien datang yang kita lakukan pertama kali adalah menentukan apa
benar pasien menderita gagal ginjal menyingkirkan diagnosis banding lainnya.
Kemudian, tentukan juga apakah gagal ginjal tersebut akut atau pun kronik. Penyakit
ginjal akut bersifat reversibel, jadi gejala yang ditimbulkan tidaklah terlalu berarti.
(Guyton, 2004). Berbeda dengan penyakit ginjal kronik yang kronis dan irreversibel,
menimbulkan manifestasi gejala pada seluruh tubuh, baik keseimbangan cairan tubuh
maupun gangguan fungsi organ. Gangguan elektrolit biasanya terjadi apabila jumlah
nefron telah berkurang lebih dari 60-70% (Ingram, 2005).
Tabel 2.2 Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik (Ingram, 2005)
Stadium GFR(ml/menit/1,73 m2) Gangguan metabolik
1 >90 Asimptomatik, kadar kreatinin mulai
meningkat
2 60-89 PTH mulai meningkat, kadar urea dan
kreatinin serum telah meningkat
3 30-59 Aborpsi kalsium menurun, malnutrisi,
hipernatremia, hipertensi, LVH, anemia,
mual, muntah
4 15-29 Hiperfosfatemia, asidosis metabolik,
peningkatan trigliserida, hiperkalemia,
pruritus
5 <15 atau memerlukan Uremia atau azotemia
dialisis
Pemeriksaan dilakukan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik,
pemeriksaan laboratorium baru melakukan pemeriksaan radiologik. Pemeriksaan
dilakukan secara bertahap untuk menyingkirkan diagnosis banding lain dan untuk
mengidentifikasi penyebab penyakit. Pada anamnesis, tanyakan gejala utama dan
gejala tambahan, anamnesis periodisitas dan kronisitas gejala. Kemudian, analisis
gejalanya secara lebih mendalam. Tanyakan juga keadaan yang mungkin menjadi
faktor resiko hipotesis awal, riwayat keluarga dan riwayat pemakaian obat-obatan
(NICE, 2008)
Gejala gangguan ginjal belum begitu tampak pada penderita gagal ginjal
akut, apalagi pada pasien stadium awal, penderita hanya akan mengeluhkan oliguria.
Keluhan penderita gagal ginjal akut biasanya lebih terorientasi pada penyakit
penyebab gagal ginjal akut. Penderita gagal ginjal akut akibat gangguan prerenal akan
mengeluhkan keadaanya yang sesak karena hipertensi, rasa haus (dehidrasi) karena
diare atau sepsis. Penderita gagal ginjal akut akibat gangguan renal akan
mengeluhkan sesuai gejala dari kerusakan ginjal. Penderita gagal ginjal akut akibat
gangguan postrenal akan mengeluhkan nyeri kolik akibat batunya ataupun Lower
Urinary Tract Syndrome akibat BPH. Akan tetapi, bila penderita gagal ginjal akut
sudah menuju ke tahap L/E dari RIFLE, gejala seperti lemah, lesu, anoreksia, mual,
muntah, gatal-gatal, rentan terhadap pendarahan bahkan bisa terjadi kejang-kejang
(Amend, 2008).
Pasien gagal ginjal kronik yang masih berada dalam stadium 1 dan 2
biasanya masih asimptomatik. Stadium 3 dan 4 terjadi poliuria, nokturia, badan
lemah, nafsu makan berkurang dan penurunan BB. Stadium 4/5 telah terjadi gejala
sistemik uremia yang nyata seperti anemia, peningkatan tekanan darah, mual, muntah,
pruritus, osteomalasia, rentan infeksi, gangguan keseimbangan air dan gejala terus
memburuk sampai indikasi transplantasi ginjal. Penderita gagal ginjal kronik dengan
komplikasi, akan mengehipertensi, anemia, osteodistrofi renal, payah jantung,
asidosis metabolik, gangguan keseimbangan elektrolit (sodium, kalium, klorida)
(Haidary, 1998).
Gejala yang dialami penderita gagal ginjal akut dan kondisi akut pada gagal
ginjal kronik biasanya sama. Bedanya, pada kondisi akut gagal ginjal kronik,
penderita akan mengeluhkan sesak nafas yang lebih berat dibanding penderita gagal
ginjal akut. Hal ini akibat komplikasi gagal ginjal kronik pada kardiovaskular yang
progresif. Selain itu, penderita gagal ginjal akut selalu mengeluhkan oliguria atau
anuria, sedangkan urinari penderita gagal ginjal kronik tahap awal masih normal atau
bahkan mengalami poliuria akibat kompensasi nefron (Sherwood, 2001).
Setelah itu, eksplorasi faktor risiko untuk menentukan penyebab. Faktor
risiko penderita Acute Kidney Injury terbanyak adalah akibat dehidrasi, hipertensi,
gagal jantung, nekrosis tubular akut dan hanya sedikit yang disebabkan obstruksi
saluran kemih. 50% dari gagal ginjal kronik disebabkan oleh diabetes mellitus, 27%
disebabkan hipertensi, 13% disebabkan glomerulonefritis dan penyebab lain hanya
berkisar 10%. Perlu ditanyakan obat-obat yang digunakan sebelumnya seperti
diuretik, NSAIDS, ACE-inhibitor, atau ARB untuk mengidentifikasi obat-obatan
yang nefrotoksik. Selain itu, riwayat keluarga penderita gagal ginjal menjadi suatu
faktor resiko penting timbulnya hal yang sama pada keturunannya (Yacoop, 2001).
Setelah anamnesis, selanjutnya lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik
dianjurkan dilakukan pada ginjal, jantung, paru dan abdomen untuk menyingkirkan
asumsi penyakit lain dan untuk menentukan apakah terdapat komplikasi pada organ
tersebut. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tanda vital, inspeksi, palpasi,
perkusi dan auskultasi (Campbell, 2002)
Pada pemeriksaan fisik prerenal gagal ginjal akut ditemukan hipertensi,
penurunan tekanan vena jugularis, berkurangnya turgor kulit, dan membran mukosa
yang kering. Untuk gangguan sirkulasi yang menyebabkan prerenal ARF, dapat
ditemukan pada pemeriksaan fisik penyakit hati kronik, gagal jantung lanjut, sepsis,
dan sebagainya(tergantung etiologi). Apabila pada kulit didapati petekie, purpura,
ecchymosis menandakan kemungkinan gagal ginjal akut yang berhubungan dengan
pembuluh darah. Ditemukannya uveitis mengindikasikan adanya nefritis interstitial
dan necrotizing vasculitis. Ocular palsy menandakan keracunan etilen glikol atau
necrotizing vasculitis (Kuypers, 2009).
Umumnya pemeriksaan fisik pada gagal ginjal kronik tidak begitu membantu
namun dapat mengetahui etiologi atau komplikasi yang telah terjadi. Hal ini
disebabkan karena pada stadium awal, penderita gagal ginjal kronik masih belum
menunjukkan kelainan apapun. Tetapi, bila sudah menimbulkan komplikasi, gejala
akan sangat parah. Pada inspeksi penderita gagal ginjal kronik akan tampak pucat.
Penderita gagal ginjal akut, kecuali gagal ginjal akut yang disebabkan anemia, tidak
akan terlihat pucat.Pemeriksaan Pada palpasi dan perkusi ginjal akan dirasakan ginjal
yang semakin mengecil. Pemeriksaan palpasi dan perkusi jantung akan menunjukkan
pembesaran ventrikel kiri. Dan identifikasi murmur saat auskultasi. Pemeriksaan
perkusi paru-paru juga sering menimbulkan bunyi redup yang menunjukkan
terdapatnya edema paru (Yacoop, 2001).
Setelah pemeriksaan fisik, lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium dan
pemeriksaan radiologik. Pemeriksaan laboratorium yang dianjurkan adalah
pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan BUN, pemeriksaan kreatinin, pemeriksaan
elektrolit dan urinalisis (protein, sedimen urin dan kultur urin bila terdapat tanda
infeksi). Untuk konfirmasi gagal ginjal termasuk gagal ginjal akut atau gagal ginjal
kronik, lakukan pemeriksaan USG. Untuk pasien yang dicurigai penderita gagal ginjal
kronik, wajib dilakukan pemeriksaan radiologik jantung berupa foto toraks maupun
EKG. Selain itu, pemeriksaan penunjang harus dilakukan juga sesuai dengan penyakit
penyerta. Misalnya, lakukan pemeriksaan KGD atau reduksi urin pada penderita DM,
faal hati (SGOT, SGPT) pada pasien dengan gangguan hati, foto polos dan IVP pada
penderita dengan gangguan ginjal atau obstruksi saluran kemih (pertimbangkan juga
kadar ureum dan kreatinin sebelum melakukan IVP) (Andreoli, 2001).
Pemeriksaan Hb bisa menjadi suatu patokan awal untuk membedakan gagal
ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Hb (normal= 12-16 g/dL) yang menurun (anemia
normokrom normositik) dijumpai pada penderita gagal ginjal kronik. Selain itu, pada
penderita gagal ginjal kronik sering juga ditemukan disfungsi platelet dan
trombositopenia akibat uremia. Pemeriksaan leukosit untuk menentukan ada tidaknya
terjadi komplikasi infeksi saluran kemih atau sepsis. Pada pasien gagal ginjal stadium
akhir biasanya menunjukkan keadaan leukopenia (Lingappa, 2003).
Peningkatan BUN (ureum normal=20-40 mg%) dan kreatinin merupakan
pertanda khas untuk gagal ginjal, baik gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronik.
Bedanya, penderita gagal ginjal akut menunjukkan penurunan ureum secara tiba-tiba,
sedangkan penderita gagal ginjal kronik menunjukkan peningkatan ureum yang
perlahan. False postive terjadi pada pasien dengan intake protein yang tinggi. BUN
juga mungkin meningkat pada pasien dengan perdarahan pada mukosa dan saluran
pencernaan, dan pengobatan steroid. Kadar kreatinin darah diperiksa untuk
menentukan stadium penyakit melalui perhitungan GFR dengan rumus: GFR
(ml/menit/1,73m2)= 186 x (Kreatinin serum)-1,154 x (Umur)-0,203 x (0,742 pada wanita)
x (1,21 pada orang kulit hitam) (Agraharkar, 2010).
Pemeriksaan protein urin pada penderita gagal ginjal akut biasanya +2 dan +
pada penderita gagal ginjal kronik. Pemeriksaan sedimen urin penderia gagal ginjal
akut bila terdapat hemautir menunjukkan eritrosit yang banyak dan silinder eritrosit.
Penderita gagal ginjal kronik menunjukkan eritrosit yang sedikit, leukosit pada urin,
waxy xast, broad renal dan failure cast (Haidary, 1998).
USG merupakan diagnosis pasti untuk membedakan gagal ginjal akut
maupun gagal ginjal kronik. Gejala akut gagal ginjal akut hampir sama dengan gejala
akut pada gagal ginjal kronik. Penting untuk membedakan kedua hal ini sebab akan
sedikit berbeda dalam prosedur diagnosis, penatalaksanaan dan prognosisnya. Yang
dinilai pada USG adalah ukuran ginjal. Pada pasien gagal ginjal kronik, ukuran
ginjalnya telah atropi sebab pengurangan nefron yang irreversibel dan digantikan oleh
jaringan ikat (fibrosis dan sklerosis). Berbeda dengan gagal ginjal akut yang
reversibel, ukuran ginjal masih tampak normal (Yacoop, 2001).
Karena komplikasi utama gagal ginjal kronik adalah gangguan gagal ginjal
kronik, pada penderita gagal ginjal kronik harus dilakukan penilaian fungsi jantung.
Biasanya pemeriksaan penunjang yang dipilih adalah foto toraks dan EKG. Biasanya,
hasil pemeriksaan akan mengarah pada pembesaran ventrikel kiri akibat hipertensi
dan anemia dan bisa juga menunjukkan gambaran gagal jantung (Campbell, 2002).
2.5. Penatalaksanaan Penyakit Ginjal Kronik
Prinsip penatalaksanaan penyakit ginjal kronik meliputi (Suwita, 2006):
Terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya
Pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid (comorbid condition)
Memperlambat perburukan (progression) fungsi ginjal
Pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskular
Terapi pengganti ginjal berupa dialisis atau transplantasi ginjal
Tabel 2.3 Rencana Tatalaksana Penyakit Ginjal Kronik Sesuai dengan Derajatnya
(Suwita, 2006)
Derajat LFG (ml/menit/1,73m2) Rencana tatalaksana
1 ≥ 90 Terapi penyakit dasar, kondisi komorbid,
evaluasi pemburukan (progression) fungsi ginjal,
memperkecil risiko kardiovaskular
2 60-89 Menghambat perburukan(progression) fungsi
ginjal
3 30-59 Evaluasi dan terapi komplikasi
4 15-30 Persiapan untuk terapi pengganti ginjal
5 < 15 Tetapi pengganti ginjal
a. Terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya
Waktu yang paling tepat untuk terapi penyakit dasarnya adalah sebelum terjadinya
penurunan LFG, sehingga pemburukan fungsi ginjal tidak terjadi. Pada ukuran ginjal
yang masih normal secara ultrasonografi, biopsi dan pemeriksaan histopatologi ginjal
dapat menentukan indikasi yang tepat terhadap terapi spesifik. Sebaliknya, bila LFG
sudah menurun sampai 20-30% dari normal, terapi terhadap penyakit dasar sudah
tidak banyak bermanfaat.
b. Pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid
Penting sekali untuk mengikuti dan mencatat kecepatan penurunan LFG pada pasien
penyakit ginjal kronik. Hal ini untuk mengetahui kondisi komorbid yang dapat
memperburuk keadaan pasien, antara lain, gangguan keseimbangan cairan, hipertensi
yang tidak terkontrol, infeksi traktus urinarius, obstruksi traktus urinarius, obat-obat
nefrotoksik, bahan radiokontras, atau peningkatan aktivitas penyakit dasarnya.
c. Menghambat perburukan fungsi ginjal
Faktor utama penyebab perburukan fungsi ginjal adalah terjadinya hiperfiltrasi
glomerulus. Cara penting untuk mengurangi hiperfiltrasi glomerulus ini adalah
(Lingappa, 2003):
Diet dengan jumlah kalori 30-35 kkal/kgBB/hari, pengaturan asupan karbohidrat
50-60% dari kalori total, pengaturan asupan lemak 30-40% dari kalori total dan
mengandung jumlah yang sama antara asam lemak bebas jenuh dan tidak jenuh,
garam 2-3 gram/hari, kalium 40-70 mEq/kgBB/hari, fosfor 5-10 mg/kgBB/hari,
dan pembatasan jumlah protein sebagai berikut:
Tabel 2.4 Pembatasan Asupan Protein dan Fosfat pada Penyakit Ginjal Kronik
(Steven, 2009):
LFG Asupan protein g/kg/hari Fosfat g/kg/hari
(ml/menit)
>60 Tidak dianjurkan Tidak dibatasi
25-60 0,6-0,8/kg/hari, termasuk ≥ 0,35 gr/kg/hari ≤ 10 g
nilai biologi tinggi
5-25 0,6-0,8/kg/hari, termasuk ≥ 0,35 gr/kg/hari ≤ 10 g
protein nilai biologi tinggi atau tambahan
0,3 gr asam amino esesial atau asam keton
< 60 0,8/kg/hari (+1 gr protein / g proteinuria ≤ 9 g
(sindrom atau 0,3 g/kg tambahan asam amino
nefrotik) esensial atau asam keton
d. Pencegahan dan Terapi Terhadap Penyakit Kardiovaskular
Pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskular merupakan hal yang
penting, karena 40-45% kematian pada penyakit ginjal kronik disebabkan oleh
penyakit kardiovaskular. Hal-hal yang termasuk dalam pencegahan dan terapi
penyakit kardiovakular adalah pengendalian diabetes, pengendalian hipertensi,
pengendalian dislipidemia, pengendalian anemia, pengendalian hiperfosfatemia, dan
terapi terhadap kelebihan cairan dan gangguan keseimbangan elektrolit. Semua ini
terkait dengan pencegahan dan terapi terhadap komplikasi penyakit ginjal kronik
secara keseluruhan.
e. Terapi pengganti ginjal berupa dialisis atau transplantasi ginjal
Terapi pengganti ginjal dilakukan pada penyakit ginjal kronik stadium V, yaitu pada
LFG kurang dari 15 ml/mnt. Terapi pengganti tersebut dapat berupa:
Hemodialisis
Gambar 2.2 Mekanisme Hemodialisis
Pada hemodialisis, darah penderita dipompa oleh mesin kedalam
kompartemen darah pada dialyzer. Dialyzer mengandung ribuan serat (fiber) sintetis
yang berlubang kecil ditengahnya. Darah mengalir di dalam lubang serat sementara
cairan dialisis (dialisat) mengalir diluar serat, sedangkan dinding serat bertindak
sebagai membran semipermeabel tempat terjadinya proses ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi
terjadi dengan cara meningkatkan tekanan hidrostatik melintasi membran dialyzer
dengan cara menerapkan tekanan negatif kedalam kompartemen dialisat yang
menyebabkan air dan zat-zat terlarut berpindah dari darah kedalam cairan dialisat.
Komplikasi akut hemodialisis adalah komplikasi yang terjadi selama
hemodialisis berlangsung. Komplikasi yang sering terjadi diantaranya adalah
hipotensi, kram otot, mual dan muntah, sakit kepala, sakit dada, sakit punggung, gatal,
demam, dan menggigil. Komplikasi yang jarang terjadi misalnya sindrom
disekuilibrium, reaksi dialiser, aritmia, tamponade jantung, perdarahan intrakranial,
kejang, hemodialisis, emboli udara, neutropenia, serta aktivasi komplemen akibat
dialisis dan hipoksemia. Kontraindikasi dari hemodialisis adalah perdarahan,
ketidakstabilan hemodinamik, dan aritmia (Wijaya, 2010)
Pasien hemodialisa harus mendapat asupan makanan yang cukup agar tetap
dalam gizi yang baik. Gizi kurang merupakan prediktor yang penting untuk terjadinya
kematian pada pasien hemodialisis. Asupan protein diharapkan 1-1,2 g/KgBB/hari
dengan 50% terdiri atas protein dengan nilai biologis tinggi. Asupan kalium diberikan
40-70 mEq/hari (Wijaya, 2010).
Indikasi dilakukannya hemodialisis pada penderita gagal ginjal stadium terminal
antara lain karena telah terjadi (Wijaya, 2010):
o Kelainan fungsi otak karena keracunan ureum (ensepalopati uremik).
o Gangguan keseimbangan asam-basa dan elektrolit, misalnya asidosis
metabolik, hiperkalemia, dan hiperkalsemia.
o Kelebihan cairan ( volume overload ) yang memasuki paru-paru sehingga
menimbulkan sesak nafas berat.
o Gejala-gejala keracunan ureum ( uremic symptoms )
Dialisis dianggap baru perlu dimulai bila dijumpai salah satu dari (Wijaya, 2010):
o Keadaan umum buruk dan gejala klinis nyata.
o K serum > 6mEq/L
o Ureum darah > 200 mg/dl
o pH darah < 7,1
o Anuria berkepanjangan (> 5 hari)
o Fluid overloaded atau kelebihan cairan yang memasuki paru-paru sehingga
menimbulkan sesak nafas berat.
Peritoneal Dialisis (PD)
Peritoneal Dialisis (beberapa orang menyebutnya sebagai 'cuci perut') merupakan
proses dialisis yang berlangsung di dalam rongga perut memanfaatkan ruang
peritoneum. Cairan dialisis/dialisat dimasukkan kedalam rongga perut melalui suatu
kateter two way (disebut Tenckhoff catheter) yang lembut, untuk kemudian didiamkan
beberapa waktu (disebut dwell time). Antara darah dengan cairan dialisis dibatasi oleh
membran peritoneum yang berfungsi sebagai media pertukaran zat. Ketika cairan
dialisat berada di dalam rongga peritoneum maka terjadi pertukaran zat-zat, yang
berguna akan terserap kedalam darah dan yang tidak berguna (produk limbah dan
racun) serta kelebihan air akan terserap kedalam cairan dialisat melalui proses
ultrafiltrasi. Ketika klep kateter pengeluaran dibuka, maka cairan dialisis
meninggalkan tubuh dengan membawa serta limbah (racun) ditambah ekstra cairan
yang tadi diserap dari dalam darah pasien (Wijaya, 2010).
Indikasi pemakaian dialisis peritoneal dapat digunakan pada pasien (Wijaya,
2010):
o Gagal ginjal akut (dialisat peritoneal akut)
o Gangguan keseimbangan cairan elektrolit atau asam basa
o Intoksikasi obat atau bahan lain
o Gagal ginjal kronik (dialisat peritoneal kronik)
o Keadaan klinis lain dimana DP telah terbukti manfaatnya
Transplantasi Ginjal
Transplantasi ginjal telah menjadi terapi pengganti utama pada pasien gagal ginjal
tahap akhir hampir di seluruh dunia. Manfaat transplantasi ginjal sudah jelas terbukti
lebih baik dibandingkan dengan dialisis terutama dalam hal perbaikan kualitas hidup.
Salah satu diantaranya adalah tercapainya tingkat kesegaran jasmani yang lebih baik.
Misalnya seorang perempuan muda yang menerima transplantasi ginjal bisa hamil
dan melahirkan bayi yang sehat. Manfaat transplantasi ginjal paling jelas terlihat pada
pasien usia muda dan pasien diabetes melitus.
Cangkok ginjal adalah mencangkokkan ginjal sehat yang berasal dari manusia
lain (donor) ke tubuh pasien gagal ginjal terminal melalui suatu tindakan bedah
(operasi). Biasanya ginjal cangkokan ditempelkan (dicangkokkan) di sebelah bawah
pada pembuluh darah yang sama dari ginjal lama yang sudah 'tidak' berfungsi
sedangkan ginjal lama dibiarkan ditempatnya (Brazy, 1989).
Tabel 2.5 Perbandingan Keuntungan Transplantasi Ginjal dan Hemodialisis Kronik
(Wijaya, 2010).
Transplantasi Ginjal HD kronik
Prosedur Biasanya satu kali Seumur hidup
Kualitas hidup Baik sekali Cukup baik
(jika berhasil)
Ketergantungan pada minimal Besar
fasilitas medic
Jika gagal Dapat HD kembali atau Meninggal
transplantasi lagi
Angka kematian pertahun 4-8 % 20-25 %
Penatalaksanaan Farmakologis Hipertensi
Terapi hipertensi pada CKD non diabetik dan CKD diabetik, level turunnya tekanan
darah sistolik dan level proteinuria dipakai sebagai diagnosis dan prognosis
progresifitas dan komplikasi CVD pada CKD (Ruggenenti, 2008).
Tabel 2.6 Rekomendasi penatalaksanaan hipertensi pemilihan obat anti hipertensi
pada CKD (Ruggenenti, 2008).
Clinical assessment of Blood Preffered Agents for CKD, Other agent to
Kidney disease Pressure with (or without) reduced CVD risk,
Target Hypertension target BP
Blood pressure > < 130/80 ACE Inhibitor or ARB Diuretik preffered
130/80 mmHg and spot then BB or CCB
urine total protein to
creatinin ratio > 200
mg/g
Blood pressure > < 130/80 No prefered Diuretik, BB or
130/80 mmHg and spot CCB
urine total protein to
craetinin ratio < 200
mg/g
Blood pressure < 130/80 ACE Inhibitor or ARB Diuretik preffered
130/80 mmHg and spot then BB or CCB
urine total protein to
craetinin ratio > 200
mg/g
Gambar 2.3 Manajemen hipertensi pada CKD (Cohen, 2008)
2.6. Komplikasi Penyakit Ginjal Kronik
Tabel 2.7. Komplikasi CKD berdasarkan derajatnya (Skorecki, 2005)
Stadium Penjelasan LFG (ml/menit) Komplikasi
1 Kerusakan ginjal ≥ 90 -
dengan LFG normal
2 Kerusakan ginjal 60-89 Tekanan darah mulai
dengan penurunan LFG meningkat
ringan
3 Penurunan LFG sedang 30-59 - Hiperfosfatemia
- Hipokalsemia
- Anemia
- Hiperparatiroid
- Hipertensi
- Hiperhomosistenemia
4 Penurunan LFG berat 15-30 - Malnutrisi
- Asidosis metabolik
- Cenderung
hiperkalemia
- Dislipidemia
5 Gagal ginjal < 15 - Gagal jantung
- Uremia
2.7. Prognosis Penyakit Ginjal Kronik
Prognosis pasien dengan penyakit ginjal kronis berdasarkan data epidemiologi
telah menunjukkan bahwa semua penyebab kematian meningkat sesuai dengan
penurunan fungsi ginjalnya. Penyebab utama kematian pada pasien dengan penyakit
ginjal kronis adalah penyakit kardiovaskuler (45%), dengan atau tanpa ada kemajuan
ke stage V.Penyebab lainnya termasuk infeksi (14%), penyakit cerebrovaskular (6%),
dan keganasan (4%). Diabetes, umur, albumin serum rendah, status sosial ekonomik
rendah dan dialisis inadekuat adalah prediktor signifikan dalam angka kematian
(Goldsmith, 2007).
Angka kematian lebih tinggi pada pasien yang menjalani dialisis dibandingkan
pada pasien kontrol dengan umur yang sama. Angka kematian setiap tahun adalah
21,2 setiap seratus pasien per tahun. Angka kelangsungan hidup yang diharapkan
pada pasien grup usia 55-64 tahun adalah 22 tahun sementara pada pasien dengan
gagal ginjal terminal angka kelangsungan hidup adalah 5 tahun (Goldsmith, 2007).
Sementara terapi penggantian ginjal dapat mempertahankan pasien tanpa waktu
dan memperpanjang hidup, kualitas hidup adalah sangat terpengaruh. Transplantasi
Ginjal meningkatkan kelangsungan hidup pasien penyakit ginjal kronik stage V
secara signifikan bila dibandingkan dengan pilihan terapi lainnya. (Kuypers, 2009)
Namun, transplasntasi ginjal ini terkait dengan mortalitas jangka pendek yang
meningkat (akibat komplikasi dari operasi). Selain transplantasi, intensitas yang tinggi
dari home hemodialysis tinggi tampak terkait dengan peningkatan ketahanan hidup
dan kualitas hidup yang lebih besar, bila dibandingkan dengan cara konvensional
yaitu hemodialiasis dan dialysis peritonial yang dilakukan tiga kali seminggu
(Skorecki, 2005).
DAFTAR PUSTAKA
Agraharkar M. Acute renal failure: overview, differential diagnosis and workup,
treatment & medication. Medscape; c1994-2010 [updated 2010 June 29; cited
2010 September 01]. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12846757.
Amend WJ, Vincenti FG. Acute renal failure; Chronic renal failure & dialysis. In:
Tanagho EA, McAninch JW, editors. Smith’s general urology 17th edition.
New York: McGraw-Hill Company; 2008. p. 520-532.
Andreoli TE, Bennett JC, Carpenter CJ, Plum F. Acute renal failure; Chronic renal
failure. In: Abdulezz SR, Bunke M, Singh H, Shah SV, editors. Cecil
essentials of medicine 4th edition. Philadelphia: WB Saunders Company;
2001. p. 231-251.
Brazy P et al. 1989. Progressionn of renal insufficiency: Role of blood pressure. Kid
Int vol 35:670-4
Campbell MF. Etiology, pathogenesis, and management of renal failure. In: Walsh
PC, Vaughan, Wein AJ, editors. Campbell urology 8th edition. Philadelphia:
WB Saunders Company; 2002. p. 273-303.
Goldsmith, David. 2007. Chronic Kidney Disease-Prevention of Progression and of
Cardiovascular Complication: ABC of Kidney Disease. Chapter 3. Blackwell
Publishing Ltd.
Guyton AC, Hall JE. Pengaturan keseimbangan asam-basa; Miksi, diuretik, dan
penyakit ginjal. In: Setiawan, editor. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Jakarta:
EGC; 1996. p. 481-503, 512-522
Haidary AL, Logan JL, Van Myck DB. Acute renal failure; Chronic renal failure. In:
Greene HL, Johnson WP, Lemke D, editors. Decision making in medicine: an
alogarithmic approach. New York: McGraw-Hill Company; 1998. p. 299-301.
Ingram RH, Brady HR, Brenner BM, Karl S, Jacob G, Singh AK. Dyspnea; Acute
renal failure; Chronic renal failure; Dialysis in the treatment of renal failure.
In: Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo LL, Jameson JL,
editors. Harrison’s principles of internal medicine 16th edition. New York:
Mc-Hill Company; 2005. p. 201-204, 1653-1667.
J.McPhee MD, Steven dkk.2009. Kidney Diseses: Current Medical Diagnosis and
Treatment. Chapter 22. United States of America: Mc Graw Hill. 2009.
CHAPTER 22
Kuypers DR. Chronic kidney disease: uremic pruritus. CME; c2009-2010 [updated
2009 Aug 19; cited 2010 September 01]. Available from:
http://cme.medscape.com/viewarticle/587670_2.
Lingappa VR. Renal disease. In: McPhee SJ, Lingappa VR, Ganong WF, editors.
Pathophysiology of disease: an introduction to clinical medicine 4th edition.
New York: McGraw-Hill Company; 2003. p. 452-462.
Matovinovic MS. 2001. Pathophysiology and Classification of Kidney Disease.
Electronic Journal of IFCC 20(1): 1-10.
http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/pdf/ckd_evaluation_classification_stratif
ication.pdf.
NICE team. Early identification and management of chronic kidney disease in adults
in primary and secondary care. NICE Clinical Guideline [serial on the
internet]. 2008 [cited 2010 September 01]; 16:[about 42 p.]. Available from:
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12069/42116/42116.pdf
Ruggenenti P et al. 2008. Role of Remission Clinic in the longitudinal treatment of
CKD. J Am Soc Nephrol ,19:1213-24
Sherwood L. Sistem kemih; Keseimbangan cairan dan asam-basa. In: Santoso BI,
editor. Fisiologi manusia dari sel ke sistem. Jakarta: EGC; 2001. p. 490-500,
520-532.
Skorecki K, Green J, Brenner BM. Chronic Renal Failure. In: Kasper DL, Fauci AS,
Longo DL, Braunwald E, Hauser SL, Jameson JL. Harrison’s Principles of
Internal Medicine. 16th ed. New York; McGraw Hill; 2005. P. 1653-63.
Suwitra K, Markum HMS. Penyakit ginjal kronik; Gagal ginjal akut. In: Sudoyo
AR, Setiyohadi N, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editors. Buku ajar ilmu
penyakit dalam jilid 1 edisi 4. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu
Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2006. p. 574-580.
Wijaya, Adi Mulyadi. 2010. Kidney or Renal Replacemnet Therapy. Available
from:http://www.infodokterku.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%2
6view%3Darticle%26id%3D68:terapi-pengganti-ginjal-atau-renal-
replacement-therapy-rrt%26catid%3D29:penyakit-tidak-
menular%26Itemid%3D18&anno=2. Accessed on: 14 November 2018
Yacoop MM, Kumar P, Clark M. Acute renal failure; Chronic renal failure. In:
Kumar P, Clark M, editors. Kumar and clark’s clinical medicine 6th edition.
Philadelphia: WB Saunders Company; 2001. p. 490-500, 659-681.
Anda mungkin juga menyukai
- Referat CKDDokumen37 halamanReferat CKDeloooyiyBelum ada peringkat
- SyokDokumen35 halamanSyokeloooyiyBelum ada peringkat
- Steroid Induced CataractDokumen13 halamanSteroid Induced CataracteloooyiyBelum ada peringkat
- Konjungtivitis ViralDokumen37 halamanKonjungtivitis ViraleloooyiyBelum ada peringkat
- TaeniasisDokumen18 halamanTaeniasiseloooyiyBelum ada peringkat
- Preeklamsia BeratDokumen37 halamanPreeklamsia BeratyuliBelum ada peringkat
- Diabetes InsipidusDokumen37 halamanDiabetes InsipiduseloooyiyBelum ada peringkat
- Syok AnafilaktikDokumen29 halamanSyok AnafilaktikeloooyiyBelum ada peringkat
- Aplikasi KMS Balita: Dalam Pemantauan PertumbuhanDokumen61 halamanAplikasi KMS Balita: Dalam Pemantauan PertumbuhaneloooyiyBelum ada peringkat
- Syok AnafilaktikDokumen29 halamanSyok AnafilaktikeloooyiyBelum ada peringkat
- Status Gizi AnakDokumen28 halamanStatus Gizi AnakeloooyiyBelum ada peringkat
- Referat Diabetes InsipidusDokumen23 halamanReferat Diabetes InsipiduseloooyiyBelum ada peringkat
- Kuesioner FixDokumen5 halamanKuesioner FixeloooyiyBelum ada peringkat
- Definisi Tugas Dan Fungsi PresenterDokumen8 halamanDefinisi Tugas Dan Fungsi PresentereloooyiyBelum ada peringkat