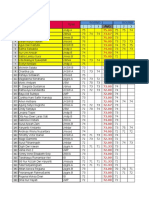Buku Kajian Pendidikan Tinggi PDF
Buku Kajian Pendidikan Tinggi PDF
Diunggah oleh
Mashun sJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Buku Kajian Pendidikan Tinggi PDF
Buku Kajian Pendidikan Tinggi PDF
Diunggah oleh
Mashun sHak Cipta:
Format Tersedia
Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Salam Ganesha!
Pendidikan sebagai hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia menjadi faktor utama
pembangunan sumber daya manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemajuan
suatu negara pun dinilai dari baiknya kualitas penduduknya dari kacamata pendidikan.
Khususnya akses pendidikan tinggi yang dijamin dengan baik penerapannya oleh negara.
Sayangnya, pendidikan tinggi sebagai salah satu elemen penting Sistem Pendidikan
Nasional yang sudah termaktub dalam UUD 1945 saat ini belum terimplementasikan dengan
baik. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia hingga saat ini belum menjamin akses pendidikan
yang luas kepada seluruh lapisan elemen masyarakat. Terjadinya gap yang besar di dalam
penerapan Pendidikan Dasar dan Menengah berbuntut pada akses pendidikan tinggi yang
tidak bisa diterima secara menyeluruh oleh anak – anak Indonesia. Kondisi ini semakin
mengkhawatirkan dengan berbagai isu – isu yang beredar terkait pendidikan tinggi di
Indonesia. Dimulai dari isu radikalisme yang disangkutpautkan dengan tujuh perguruan tinggi
negeri besar, penerapan Student Loan yang tidak mengentaskan akar masalah, hingga
kebijakan pemungutan biaya pendidikan tinggi melalui uang pangkal yang memberatkan
mahasiswa.
Menilai kondisi pendidikan tinggi Indonesia yang memprihantikan ini, Keluarga
Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) bersikap secara tegas bahwa Sistem
Pendidikan Nasional Indonesia perlu dibenahi secara menyeluruh dan dengan komitmen
penuh seluruh pihak. Khususnya terkait implementasi pendidikan tinggi dan segala hal yang
terkait dengannya. Jangan sampai hanya karena kepentingan politik semata yang menyertai
pendidikan tinggi di Indonesia, Sistem Pendidikan Nasional terciderai begitu saja. Semua
untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia melalui pencerdasan kehidupan bangsa
dengan pendidikan.
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 2
Akhir kata, semoga seluruh pihak sadar dan bergerak untuk memperjuangan tujuan negara
kita dalam konteks pendidikan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan kekuatan dalam
memperjuangkannya.
Untuk Tuhan, Bangsa dan Almamater
Presiden KM ITB
Ahmad Wali Radhi
Narahubung: Galih Norma (085234456398)
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 3
Daftar Isi
Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………..2
Konten Pencerdasan Terkait Radikalisme ………………………………………………..5
Konten Pencerdasan Terkait Student Loan ……………………………………………13
Konten Pencerdasan Terkait Biaya Pendidikan ……………………………………..21
Kata Penutup …………………………………………………………………………………………25
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 4
Konten Pencerdasan Terkait Radikalisme
“Aktivisme bukanlah tindakan radikal. tindakan represif terhadap aktivisme bukanlah
jalan keluar”
Kementrian Kebijakan Nasional KM ITB 2018-2019
Kebebasan berpikir dan berpendapat adalah komponen utama yang menguji daya
kritis yang dimiliki sebagai komponen utama mahasiswa. Kebebasan berpikir ini seringkali
dipandang sebagai bibit-bibit pemicu gerakan radikalisme. Seperti pada terjadinya kasus
pemberangusan kebebasan berpendapat yang dilakukan ormas-ormas tidak bertanggung
jawab seperti kasus pembubaran diskusi Marx di kampus ISBI 1.Isu mengenai radikalisme dalam
kehidupan kemahasiswaan sudah lama mencuat semenjak 2011 dengan terbitnya artikel
“Radikalisme Mengincar Kampus” oleh Ansyaad Mbai yang menjabat kepala BNPT kala itu.
Artikel tersebut memuat bahwa radikalisme menyusup ke lingkungan kampus dengan
memanfaatkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah. Tindakan dan klaim
seperti ini menurut pengamat Terorisme Harits Abu Ulya menilai : “tidak boleh hanya karena
ada satu-dua orang oknum mahasiswa satu kampus terlibat aksi terror kemudian dibuat dasar
untuk menggeneralisir untuk semua kampus”.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh pengamat terorisme lainnya, Al Chaidar.
Menurutnya penyebaran radikalisme jangan sampai menciderai arti pola pikir kritis khas
mahasiswa. Kampus merupakan tempat dimana kebebasan akademis perlu dihormati, apapun
bisa dibahas sebagai bagian dari aktivias intelektual dan pengembangan kelimuan. Kajian-
kajian berbagai hal mengenai keislaman, kesosialismean, marzisme, feminism, globalisme,
liberalism, dan LGBT pun adalah hal yang lumrah. Kajian tersebut dipahami dalam konteks
berdialektika dalam koridor pemikiran semata, tidak serta merta mahasiswa yang
bersangkutan penganut paham/idiologi terkait2.
Penjelasan berikutnya akan memaparkan lebih lanjut mengenai perbedaan antara
aktivisme, radikalisme, dan terorisme. Karena ketiga hal ini seringkali tercampur aduk dan
menjadi legitimasi tindakan represif terhadap golongan masyarakat tertentu. Pada akhir
penjelasan akan dipaparkan juga mengenai kecenderungan tindakan represif yang sengaja
dilakukan oleh pemerintah.
1
https://www.merdeka.com/peristiwa/diskusi-karl-marx-di-kampus-isbi-bandung-dibubarkan-fpi.html
2
https://nusantara.news/klaim-bnpt-soal-kampus-terpapar-radikalisme-perlu-parameter-jelas/
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 5
Aktivisme, Radikalisme, dan Terorisme
Untuk dapat mendefinisikan perbedaan antar ketiga hal ini, dapat dimulai dengan
penjelasan partisipasi politik. Berdasarkan jurnal “On Radicalisme : A Study of Political Mehods
in The Shadow Land Between Activism and Terrorism” oleh Sophie Sjoqvist, mengungkapkan
bahwa pada awalnya partisipasi politik didefinisikan sebatas pada aktivitas yang dilakukan oleh
individu-individu dalam masyarakat yang bertujuan untuk memengaruhi pemilihan anggota
pemerintah dengan kata lain adalah pemilu. Namun seiring dengan berkembangnya zaman
definisi partisipasi politik semakin meluas sampai kepada gerakan boykot, demonstrasi, diskusi
di ruang publik yang tergolong sebagai cara tidak konvensional. Sehingga ketika kita
berdiskusi mengenai suatu topik di media massa yang merupakan ruang publik virtual, kita
sudah ikut berpartisipasi dalam hal politik. Cara-cara seperti ini merupakan bentuk aktivisme
politik untuk tujuan-tujuan tertentu, contoh saja dengan adanya organisasi-organisasi yang
didirakan oleh masyarakat sendiri/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti LBH (Lembaga
Bantuan Hukum), JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), bahkan pergerakan kemahasiswaan
itu sendiri. Banyak dari gerakan aktivis berakhir dengan metode demonstrasi karena cara-cara
konvensional untuk duduk bertemu dengan pihak berwenang dianggap tidak membuahkahn
hasil.
Seringkali kita melihat di media massa bahwa demonstrasi diakhiri dengan kericuhan,
sehingga seringkali aktivisme dianggap sebagai sesuatu yang illegal dan cenderung radikal.
Nyatanya aktivisme seringkali terjebak oleh tindakan represif dari pihak berwenang (yang akan
dijelaskan di akhir artikel) dan framing media massa. Contoh saja aksi demonstrasi damai yang
dilakukan oleh warga Taman Sari Kota Bandung yang mengalami kekerasan fisik 3. Secara
diagramatik partisipasi politik dapat dibagi menjadi tiga bagian besar sebagai berikut :
3
http://ayobandung.com/read/20180307/64/29711/bentrokan-dalam-mencari-keadilan-untuk-tamansari
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 6
Gambar 1. Pembagian Partisipasi Politik dengan Fokus Radikalisme
Partisipasi
Politik
Aktivisme
Politik
Aktivisme Radikalisme Terorisme
Sumber : (Sjoqvist, 2014)
Terdapat perbedaan karateristik pergerakan antara aktivisme, radikalisme, dan
terorisme. Aktivisme merupakan tindakan yang menggunakan metode legal sesuai aturan,
sedangkan radikalisme mencakup sampai dengan tindakan ilegal. Tetapi terdapat
permasalahan dengan tindakan yang tergolong ilegal/membuat keonaran karena dapat
memberikan makna rancu yang mempermudah pihak berkuasa dalam menghentikan jenis
partisipasi politik tersebut.
Dua kutub berbeda antara Aktivisme dan Radikalisme
Elizabeth Verardo dalam artikelnya yang berjudul “Political Radicalism : A Continuing
Challenge to Democracy” mengungkapkan bahwa radikalisme bukanlah sebuah gerakan lebih
ekstrim dari aktivisme, tetapi berada pada dua kutub yang berbeda. Intensi dari aktivisme
adalah memperjuangkan kepentingan politik dengan cara legal. Radikalisme juga memiliki
tujuan yang sama, tetapi memiliki kecenderungan pergerakan yang menjustifikasi kekerasan
politik sebagai langkah memungkinkan untuk merubah struktur politik. Gerakan-gerakan
radikal ini salah satunya dipicu oleh gejolak politik akibat kebutuhan dasar dan kesetaraan
yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah. Fenomena “Arab Spring” yang melanda 12
negara di Timur Tengah4.
Lebih lanjut lagi, dalam membedakan antara aktivisme dan radikalisme tidak bisa
hanya sampai kepada metode legal dan illegal yang dilakukan, karena seringkali pergerakan
aktivisme dianggap sebagai illegal oleh pihak berwenang. Sehingga dalam membedakan
antara aktivisme dan radikalisme dapat dibedakan dalam aspek penegakan hukum kepada
pihak terkait. Sophie Sjoqvist mengungkapkan bahwa jika demonstrasi yang dilakukan oleh
aktivis berakhir ricuh dan mengakibatkan kerugian (yang merupakan hal tak terhindarkan) dan
4
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-12813859
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 7
pihak tersebut mau untuk diproses secara hukum, maka gerakan tersebut masih dikategorikan
aktivisme, karena individu/pihak bersangkutan tunduk dalam konstitusi/peraturan legal
berlaku. Tetapi jika pihak yang melakukan tindakan ilegal tidak bersedia menghadap hukum
maka dapat dikategorikan radikal (menganggap bahwa hukum yang berlaku di suatu negara
tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan paham yang dimiliki.
“Radikalisme” Revolusi Perancis 1848
Radikalisme terkadang diperlukan untuk suatu momentum tertentu (radikalisme dalam
hal ini terlepas dari segala ideologi yang teranut di dalamnya, melainkan sebagai bentuk dari
aktivisme politik) seperti revolusi Perancis pada tahun 1848. Berdasarkan jurnal
“Industrialization and Social Radicalisme : British and French Workers’ Movement and The Mid-
Nineteenth Century Crises” oleh Craig Calhoun mengemukakan bahwa radikalisme merupakan
bentuk perlawanan terhadap agitasi politik suatu rezim. Jika terdapat asumsi bahwa
radikalisme hanya terjadi pada golongan masyarakat yang tidak terdidik dan minim
pengendalian diri, hal tersebut adalah keliru, karena radikalisme terjadi di Perancis yang
mengalami proses industrialisasi. Gerakan radikal terhadap pemerintah muncul akibat
ketidakpuasan dan eksploitasi terhadap golongan pekerja. Sehingga para pekerja bersatu
dalam Revolusi Perancis Februari 1848 yang mampu menghilangkan tindakan represif
pemerintah terhadap rakyat kecil. Tindakan radikal sebagai sesuatu yang buruk tidak bisa
dipandang secara hitam putih, karena bentuk radikalisme menjadi titik kulminasi perjuangan
untuk melawan pemerintah yang menyengsarakan.
Radikalisme dan Terorisme
Menurut Sophie Sjoqvist mengungkapkan bahwa definisi dari terorisme adalah
tindakan yang menyebabkan kematian, cedera serius yang merugikan masyarakat sipil dengan
tujuan untuk mengintimidasi penduduk atau pemerintah atau organisasi di luar pemerintah
untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Hampir serupa dengan definisi
tersebut, pemerintah dalam RUU Terorisme yang sudah disahkan mengeluarkan definisi
terorisme sebagai :
”Terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang
menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban
yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek
vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif
politik, ideologi, atau gangguan keamanan”. (definisi ini masih menuai perdebatan karena
melibatkan motif politik, idelogi yang dianggap multiinterpretatif5)
5
https://katadata.co.id/berita/2018/05/15/definisi-terorisme-tuai-perdebatan-di-pansus-ruu-antiterorisme
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 8
Jika dirangkum, perbedaan antara aktivisme, radikalisme, dan terorisme sebagai berikut :
Activism Radicalism Terrorism
The usage of legal methods The usage of illegal acts to The use of deadly violence or
and civilian disobedience to reach political goals. The violence that seriously harms
reach political goals. For an performer is not willing and its victims against unspecific
illegal act to be classified as does not mean to face the civilian or non-combatants
civilian disobedience, they consequences of the illegal who are not aware of why
have to be performed openly, acts. These acts include they are being attacked and
without violence and with the physical violence but are only are unlikely to reciprocate to
intention of facing its used against specific groups the attack themselves.
consequences individually or individually who are aware
according to the laws of the of why they are being
state it is commited in. attacked and are likely to
reciprocate individually
against attacker.
Sumber : (Sjoqvist, 2014)
Langkah Represif terhadap tindakan aktivisme.
Kejadian pengepungan Gedung LBH Jakarta oleh ormas Anti-PKI pada bulan
September 2017 menunjukkan salah satu tindakan represif yang dilakukan oleh golongan
masyarakat tidak bertanggungjawab dan polisi juga tidak berdaya dalam melindungi
kebebasan berdiskusi masyarakat (diskusi sama sekali tidak berusaha menyebarkan paham
komunisme, diskusi ini bertemakan ‘Darurat Demokrasi’ di Indonesia 6). Di Indonesia bukan
hanya organisasi masyarakat yang melakukan tindakan represif, tetapi pemerintah juga
melakukannya. Pada hari Selasa, 22 November 2016, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat
memutuskan bahwa aparat kepolisian telah melakukan tindakan represif bahkan kriminalisasi
terhadap 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi hukum dalam demonstrasi damai menolak
PP Pengupahan di Jakarta7. Aparat kepolisian terbukti melakukan pengeroyokan, kekerasan,
pengerusakan mobil komando, penangkapan sewenang-wenang, hingga penghilangan
barang milik 26 aktivis. Majelis Hakim menguatkan bahwa tindakan aparat bertentangan
dengan hak berpendapat di muka umum yang diatur dalam UU No. 9 tahun 1998.
Sebenarnya apa definisi dari represifitas, dan mengapa tindakan represi dilakukan oleh
suatu golongan, terkhususnya pemerintah? Menurut Jacqueline deMerit dalam riset
6
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170918073733-20-242364/kronologi-pengepungan-gedung-lbh-
jakarta-oleh-massa-anti-pki
7
https://www.bantuanhukum.or.id/web/aparat-kepolisian-terbukti-melakukan-kriminalisasi/
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 9
Universitas Oxford yang berjudul “The Strategic Use of State Repression and Political Violence”
mengungkapkan bahwa represi merupakan tindakan memaksa suatu pihak dengan dorongan
institusional ataupun fisik. Tindakan represif seringkali melanggar hak asasi manusia, secara
sistematik perilaku ini kerap dilakukan oleh pihak berkuasa/pemerintah untuk mencapai tujuan
politik tertentu yang berlandaskan pada rasionalitas tersendiri. Represi dapat dilakukan
dengan kekuatan militer, ataupun organisasi bayaran selama mereka dianggap sebagai pihak
fungsional yang memiliki legitimasi atas perpanjangan tangan dari pemerintah. Tujuan akhir
dari represi adalah untuk melawan balik segala ancaman internal yang muncul.
Tindakan represif dapat terjadi sesuai dengan rezim kekuasaan yang berlaku. Negara
yang menganut sistem demokrasi dengan baik tidak perlu melakukan tindakan represif,
melainkan memberikan alternatif dengan adanya partisipasi dan kontestasi. Cara ini
meminimalisir terjadinya tindakan represi oleh pemerintah, karena setiap pendapat dapat
terakomodasi oleh komunikasi antar pihak. Dengan sistem demokrasi ini rakyat tidak perlu
takut untuk di represi oleh pemerintah, karena suara kebanyakan jika tidak puas dapat
menghengkangkan pemerintah dari kekuasaannya. Pada lain kutub, pemerintahan yang
otoriter juga tidak perlu melakukan tindakan represif kepada rakyatnya, karena rakyat sudah
pasti akan patuh dan enggan untuk mengkritik pemerintah sedari awal. Tindakan represif
justru ditemukan di sebuah negara yang setengah-setengah dalam mengimplementasikan
demokrasi dan tetap otoriter dalam menjaga kekuasaan.
Lalu mengapa tindakan represif masih saja dilakukan? Represi adalah tindakan yang
mudah (secara substantif) dan murah (secara prosedural) untuk dilakukan. Secara substantif
akomodatif berusaha untuk bekerja sama dengan oposisi dan memberinya kesempatan politik
yang sama. Secara prosedural berbeda dengan presedur akomodatif yang dapat dilakukan
untuk menenangkan tensi politik dengan melakukan diskusi, memberikan amnesti, reshuffle
kepemimpinan. Tindakan yang bersifat akomodatif merupakan tindakan yang butuh proses
dan mahal, karena musyawarah untuk mencapai mufakat membutuhkan waktu lama juga alot.
Sehingga mudah saja untuk meredam suara-suara kritik oposisi dengan mendelegasikan tugas
pembubaran diskusi kepada aparat tertentu.
Menjadi pertanyaan berikutnya, apakah represi merupakan tindakan yang buruk untuk
dilakukan? Sangat banyak buruknya dibandingkan proses akomodatif. Terdapat sebuah
asumsi bahwa tindakan represi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak
diinginkan di masa depan, justru malah akan semakin menyebar dan terjadi. Sesuai dengan
hipotesis "backlash" bahwa tindakan represif justru akan memobilisasi setiap pihak yang dapat
berujung pada demonstrasi besar-besaran melalui pergerakan mikro dan difusi spasial.
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 10
Persepsi Pemerintah terhadap Gerakan “Radikal?”
Pada tanggal 31 Mei 2018 BNPT bersama Kemenristekdikti mengeluarkan daftar
kampus-kampus yang terpapar radikalisme. Klaim ini menuai banyak kecaman dan pertanyaan
dari setiap kampus yang dinyatakan sebagai kampus radikal di dalamnya. Kemudian pada
tanggal 7 Juni 2018 Menristek M Nasir menegaskan bahwa klaim tersebut hanyalah baru
dugaan semata8. Penetapan kampus-kampus yang terpapar radikalisme ini masih belum
memiliki parameter dan indikator yang jelas. Tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat,
standar apa yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan sebuah perkumpulan radikal
atau tidak? Perisitiwa ini menjadi sebuah pengingat yang nyata bahwa pemerintah saat ini
memiliki kecurigaan terhadap gerakan kemahasiswaan. Kabarnya Kemenristekdikti juga akan
memanggil rektor-rektor dari setiap universitas untuk membahas isu ini 9. Hingga saat ini
belum terdapat perbincangan antara pemerintah dengan pergerakan kemahasiswaan
Indonesia dalam merumuskan secara bersama batasan tindakan radikal. Pemerintah masih
bergantung terhadap bentuk kebijakan yang top-down dengan belum mendengarkan
pendapat dari aktor utama yang menjalankan pergerakan kemahasiswaan, yakni mahasiswa.
Tindakan pemerintah untuk memonitoring media sosial mahasiswa dalam rangka
mewujudkan kampus yang steril, bersih, dan aman dari segala bentuk paham radikal
dipandang berlebihan oleh pengamat pendidikan dari Universitas Al Azhar, Prof Supraji
Ahmad10. Langkah ini tidak hanya mengintervensi hak privasi mahasiswa, tetapi langkah ini
menunjukkan bahwa pemerintah masih berfokus pada gejala yang terjadi di permukaan saja.
8
https://news.detik.com/berita/4057461/menristek-jelaskan-kabar-7-kampus-negeri-ternama-terpapar-
radikalisme
9
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180606165229-20-304059/menristek-kumpulkan-rektor-bahas-
radikalisme-kampus-25-juni
10
https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/06/05/p9u3c7430-pengawasan-hp-dan-
medsos-mahasiswa-dinilai-berlebihan
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 11
Penutup
Pada akhirnya Indonesia sebagai negara demokratis yang dilandakan oleh Pancasila
memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap masyarakatnya dengan adil dan beradab.
Tindakan-tindakan represif terhadap gerakan aktivisme bukanlah langkah yang bijak untuk
dilakukan. Memang betul sejatinya setiap bentuk terror yang menempatkan kehidupan
masyarakat sipil terancama haruslah diberantas secara tuntas. Namun jangan sampai
kebebasan dalam mengemukakan pendapat di muka umum, berdiskusi mengenai topik-topik
tertentu untuk memperlebar wawasan, dan bahkan berikir pun di halang-halangi melalui
tindakan represif dengan dalih pemberantasan gerakan radikal dan terror.
Kemahasiswaan memiliki kemandirian dalam mengatur segala tata nilai yang diatur
bersama, bentuk pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah seharusnya
melibatkan mahasiswa. Pemerintah tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan dalam
pengawasan gerakan kemahasiswaan yang membatasi proses berpikir kritis mahasiswa,
karena pada akhirnya yang mengetahui kegiatan kemahasiswan adalah mahasiswa itu sendiri.
Oleh karena itu pemerintah dan perkumpulan mahasiswa harus duduk bersama agar terjadi
musyawarah yang saling menguntungkan dan mendukung kedua belah pihak. Mahasiswa
bukanlah oposisi dari pemerintah, sebaliknya kita adalah rekan kerja bersama dalam
membangun Bangsa Indonesia dengan saling mengkritisi satu sama lain.
Daftar Pustaka
Calhoun, C. (1983). Industrialization and Social Radicalism : British and French Workers'
Movement and The Mid-Nineteenth-Century Crises. Theory and Society, Vol 12, No. 4, 485-
504.
deMeritt, J. H. (2016, October 1). The Strategic Use of State Repression and Political Violence.
Contentious Politics and Political Violence, pp. 1-23.
Sjoqvist, S. (2014). On Radicalism : A Study of Political Methods in the Shadow Land Between
Activism and Terrorism. Uppsala: Uppsala University.
Verardo, E. (2016). Political Radicalism : A Continuing Challange to Democracy. New Haven:
Yale University.
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 12
Konten Pencerdasan Terkait Student Loan
“Sistem pendidikan yang diserahkan kepada pasar”
Kementrian Kebijakan Nasional KM ITB 2018-2019
Student Loan
Reformasi 1998, adalah sebuah momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, pada momen ini
Indonesia memulai langkah pertamanya dalam memasuki periode demokrasi dengan
perpolitikan yang merdeka dan liberal. Reformasi 1998 tentu tidak bisa dilepaskan dari
pergerakan mahasiswa. Mahasiswa sebagai motor penggerak reformasi yang menggulingkan
pemerintahan Orde baru adalah fakta yang sudah umum diketahui di Indonesia.
Dengan ini, sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa sebagai buah dari
pendidikan dapat membawa atau memantik perubahan-perubahan besar bagi negara
Indonesia sendiri. Oleh karena itu, di momen 20 tahun reformasi ini, sudah sepantasnya kita
menengok kembali kabar sistem Pendidikan yang mencetak calon-calon pemberi perubahan
tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018 mengompilasi
berbagai kajian mengenai pendidikan dari BEM KM UGM, BEM KM UNY, BEM UNSOED, dan
Kabinet KM ITB sendiri untuk membuat sebuah catatan refleksi sistem pendidikan yang
ditinjau berdasarkan kondisi penyelengaraan pendidikan tinggi serta pendidikan dasar dan
menegah.
Untuk Pendidikan tinggi, topik yang menjadi sorotan adalah mengenai student loan
yang yang menimbulkan polemik akan keberadaan negara dalam menjamin Pendidikan
terjangkau bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan penerapan student loan sendiri yang jika
dianalisis dampaknya dapat berpengaruh besar untuk Indonesia itu sendiri dan butuh
persiapan dan kerja sama yang cukup matang oleh para penyelenggaranya. Sementara itu,
untuk pendidikan dasar dan menengah, topik yang menjadi sorotan ada tiga, yakni : 20%
Anggaran untuk Pendidikan, Kondisi Guru Saat ini, dan UU wajib belajar 12 tahun.
Student Loan dalam Perspektif Hukum
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4
tercantum kewajiban-kewajiban Pemerintah Negara Indonesia yang salah satunya adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Pasal 31 UUD Negara Kesatuan Republik
Indonesia ayat 1 berbunyi ‘Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selain itu,
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 13
dalam Pasal 28C UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia ayat 1 berbunyi ”Setiap orang
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dari hal
tersebut, jelas bahwa pemerintah memiliki kewajiban terhadap rakyatnya untuk menyediakan
pendidikan yang baik dan layak sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia.
Berdasarkan Kemenristekdikti, perguran tinggi memiliki tanggung jawab sosial
pendidikan tinggi yang salah satunya universitas baik negeri maupun swasta tidak sungkan
menerima mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Apalagi pemerintah telah
mewajibkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan semua perguruan tinggi negeri wajib
menerima 20% mahasiswa tidak mampu dari total mahasiswa yang diterimanya.
Kewajiban pemerintah dan perguruan tinggi yang telah disebutkan diatas kemudian
juga ditegaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal
76 ayat (1) yang menekankan bahwasannya pemerintah pusat dan daerah, serta perguruan
tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. Apabila
pemenuhan hak tersebut dialihkan kepada selain dari pihak-pihak yang disebutkan dengan
tegas oleh undang-undang (misal bank), maka sudah sangat jelas terjadi pengingkaran
terhadap kewajiban, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Perguruan Tinggi.
Selanjutnya, pada undang – undang dan pasal yang sama ayat 2, diberikan beberapa
bentuk pilihan metode pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan oleh pihak-pihak yang
bertanggung jawab. Pilihan metode yang dimaksud adalah berupa beasiswa kepada
mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan, pinjaman dana tanpa
bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Hal tersebut
memperlihatkan bahwa sebenarnya Undang-Undang ini tidak menutup kesempatan bagi
pemerintah untuk melakukan pinjaman dana kepada peserta didik. Namun, pada frasa
selanjutnya terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam mekanisme peminjaman dana
tersebut, yakni tanpa bunga dan wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.
Pada akhirnya, penerapan student loan bermasalah dengan poin “tanpa bunga” pada syarat
tersebut karena sistem pendanaan yang diberikan kepada bank.
Usaha Pemerintah Menurunkan Suku Bunga Hingga 0%
Untuk mengatasi permasalahan frasa “tanpa bunga” seperti yang telah disebutkan
sebelumnya, pemerintah mengaku masih mengkaji rencana mekanisme student loan agar
bunga yang diberikan dalam setiap peminjaman yang masih berada dalam kisaran 6 % bisa
menjadi 0 %. Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sulaiman
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 14
Arif Arianto menyatakan bahwa penerapan bunga 0 % pada kredit Pendidikan adalah hal yang
tidak mungkin. Menurutnya, program kredit pendidikan saat ini berbeda dengan KMI dahulu
yang sumber dananya yang berasal murni dari cadangan negara sementara untuk kredit
pendidikan berasal dari dana pihak ketiga bank. Sementara itu, menurut Direktur Penelitian
Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, bunga untuk student loan
memang idealnya 0% tanpa agunan, namun untuk meminimalkan risiko kredit (pembahasan
lebih lanjut berada di pembahasan implikasi penerapan student loan) perlu ada sistem
penjaminan yang tepat dari pemerintah, serta sistem seleksi dan monitoring yang memadai
bagi para penerima kredit. Dengan demikian, pemerintah perlu juga mengalokasikan
anggaran untuk sistem penjaminan kredit pendidikan.
Student Loan dalam Perspektif Ekonomi dan Kesiapan Indonesia
Penerapan Student Loan dapat menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif jika
ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Salah satu dampak positif adalah peningkatan kualitas
SDM masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dikeluarkan oleh University
of Pensylvania yang menyatakan bahwa pemberlakuan kredit pendidikan di negara
berkembang dapat membantu meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan tingkat
partisipasi pendidikan tinggi. Selain itu, Presiden Jokowi juga menargetkan dengan adanya
kebijakan student loan ini masyarakat Indonesia mampu menggeser aktivitas kreditnya dari
konsumtif untuk keperluan produktif seperti pendidikan.
Namun, penerapan student loan juga memiliki risiko yang nilainya, menurut Direktur
Penelitian Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, bergantung
pada sejumlah faktor, terutama kepastian peminjam student loan mendapatkan pekerjaan
setelah lulus yang memengaruhi kemampuan peminjam dalam pengembalian dana. Untuk itu,
adanya program kredit pendidikan perlu dibarengi dengan evaluasi kurikulum pendidikan
tinggi sehingga para lulusan perguruan tinggi benar-benar siap kerja setelah lulus dan
memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut, kita perlu
memperhatikan jumlah pengangguran terbuka yang masih tinggi. Berikut adalah data yang
terdapat di BPS terkait tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang
ditamatkan pada tiga tahun terakhir.
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 15
Tabel 1 Perbandingan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dengan Pengangguran Terbuka
Pengangguran Terbuka Menurut
Pendidikan Tertinggi yang
Pendidikan Tertinggi
Ditamatkan (Orang)
Yang Ditamatkan +
Total
2015 2016 2017
Tidak/belum pernah
55554 59346 62984
sekolah
Tidak/belum tamat SD 371542 384069 404435
SD 1004961 1035731 904561
SLTP 1373919 1294483 1274417
SLTA Umum/SMU 2280029 1950626 1910829
SLTA Kejuruan/SMK 1569690 1520549 1621402
Akademi/Diploma 251541 219736 242937
Universitas 653586 567235 618758
Total 7560822 7031775 7040323
Jika dilihat berdasarkan data BPS diatas, tingkat pengangguran dalam tiga tahun
terakhir terbilang tinggi. Terutama pada data terakhir pada tahun 2017 untuk lulusan diploma
tingkat pengangguran mencapai 3.4507% dari total jumlah pengangguran. Sedangkan untuk
lulusan universitas, tingkat pengangguran bulan mencapai 8.7888%. Angka pengangguran
baik untuk lulusan diploma ataupun universitas terbilang tinggi.
Jika skema student loan tetap dilakukan dalam kondisi pengangguran sarjana/diploma
yang masih tinggi, maka kemungkinan ketidaksanggupan membayar peminjam sebagai
peminjam akan sangat tinggi yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan bayar kredit dan
berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 16
Kemudian, hal yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah permasalahan biaya kuliah.
Tujuan diadakannya student loan ini adalah agar mahasiswa yang kesulitan dalam
permasalahan biaya kuliah dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Namun berdasarkan
hipotesis milik Melo dan Zarruk dari University of Pennsylvania, kebijakan student loan dapat
mempengaruhi penetapan biaya kuliah dalam arah yang kurang mendukung tujuan tersebut
di waktu yang akan datang (kenaikan biaya kuliah). Hipotesis tersebut mengatakan bahwa
pola awal dari kredit pendidikan adalah permintaan (demand) yang semakin tinggi terhadap
pendidikan tinggi. Pola kedua adalah biaya kuliah yang secara perlahan naik mengikuti
permintaan. Pola terakhir adalah munculnya institusi-institusi pendidikan baru yang lebih
banyak dengan pola yang sama.
Selain itu, riset Albrecht dan Ziderman pada tahun 1991 terkait review program
pendidikan di 24 negara, baik di negara maju dan berkembang juga perlu menjadi bahan
pertimbangan dalam kebijakan penerapan student loan. Berdasarkan hasil risetnya, negara
maju pada umumnya mampu mendapatkan keuntungan dari selisih bunga pinjaman
pemerintah ke pasar keuangan dengan beban bunga kepada mahasiswa sebagai biaya
operasional karena biaya modal yang terbilang rendah namun biaya manusia terbilang tinggi.
Sedangkan untuk negara berkembang justru sebaliknya dimana pada umumnya belum
memiliki sistem administrasi pajak yang baik, kependudukan dan penegakan hukum yang
kurang memadai, mahalnya biaya modal namun biaya manusia yang murah, yang
mengakibatkan tingkat gagal bayar atas utang pendidikan terbilang tinggi. Penelitian lain
terkait student loan yang tidak cocok untuk negara berkembang salah satunya data yang
ditunjukkan oleh Chapman dan Lounkaew menunjukkan perbandingan tingkat gagal bayar 4
negara yaitu: Amerika Serikat, Kanada, Thailand, dan Malaysia, yang menunjukkan persentase
14,7%, 13%, 53% dan 49%. Mereka menyatakan perbedaan yang tinggi pada gagal bayar
antara negara maju dan berkembang terletak pada rendahnya pendapatan manusia dan
sistem administrasi yang buruk.
Repayment Ratio dan Skema Perhitungan
Berdasarkan working paper yang berjudul “Student loans repayment and recovery:
international comparisons” milik Adrian Ziderman dan Hua Shen yang dilakukan tahun 2008
repayment ratio Indonesia pada tahun tersebut sebesar 27.56% yang artinya mahasiswa yang
mampu melunaskan hutang pendidikannya hanya sebesar 27.56% dari total nominal hutang
yang mampu dibayar kembali ke peminjam. Sedangkan untuk sisanya atau sekitar 72.44%
menjadi beban keuangan negara karena peminjam tidak mampu melunaskan sisa hutangnya.
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 17
Tabel 2 Hidden Grant and Repayment Ratios, Selected Countries
Jika dilakukan asumsi uang kuliah yang dibutuhkan sekitar 8 juta rupiah persemester,
dikalikan 8 semester maka kurang lebih dibutuhkan pinjaman sekitar 64 juta rupiah. Pinjaman
tersebut belum termasuk kebutuhan makan, transportasi, tempat tinggal, dan lain-lain. Saat
ini, Bank BTN telah melakukan peluncuran dana kredit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan
hingga 200 juta rupiah dengan bunga 6.5% flat selama lima tahun. Jika diasumsikan peminjam
melakukan kredit pendidikan bunga bank dilakukan di Bank BTN maka, contoh perhitunganya:
Pokok pinjaman: Rp. 64.000.000 Bunga pertahun/perlima tahun: 1.3%/6.5% Tenor
Pinjaman: 60 bulan Bunga perlima tahun: 6.5% X Rp. 64.000.000 = Rp. 4.160.000 Total
pengembalian: Rp. 68.160.000 Angsuran Perbulan; Rp. 68.160.000/60 = RP. 1.136.000
Dari skema perhitungan diatas, angsuran perbulan yang harus dibayarkan peminjam
terhitung Rp. 1.136.000. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2016 terkait rata-rata upah
pegawai yang bekerja sebagai tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya adalah sebagai
berikut:
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 18
Tabel 3 Perbandingan rata-rata gaji dan pendidikan tertinggi
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan
Pendidikan Tertinggi Utama (Rupiah)
- UB
Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis
2016
Februari Agustus
Tidak/belum pernah
- Rp400,000
sekolah
Tidak/belum tamat SD Rp610,876 Rp2,052,972
Sekolah Dasar Rp1,466,192 Rp1,394,592
Sekolah Menengah
Rp1,367,792 Rp1,421,082
Pertama
Sekolah Menengah
Rp1,635,401 Rp1,698,891
Atas (Umum)
Sekolah Menengah
Rp2,184,118 Rp2,629,860
Atas (Kejuruan)
Diploma
Rp2,641,067 Rp2,945,882
I/II/III/Akademi
Universitas Rp3,299,446 Rp3,652,015
Rata-Rata Rp2,847,016 Rp3,199,062
Jika dilihat dari data BPS, untuk lulusan diploma dan universitas dengan masing-
masing gaji rata-rata pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp.2.945.882 dan Rp.3.652.015, dengan
kewajibannya untuk membayar angsuran sebesar Rp. 1.136.000, maka sisa uang yang dimiliki
setelah membayar pinjaman sebesar Rp. 1.809.882 untuk lulusan diploma dan Rp. 2.516.015
untuk lulusan universitas.
Asumsikan dengan sisa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup
perbulan di daerah perkotaan contohnya saja di DKI Jakarta berdasarkan hasil survey oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sepanjang
tahun 2017 sebesar Rp.3.149.631. Jika dihitung dengan sisa uang yang masih ada setelah
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 19
membayar kredit pendidikan maka untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di Jakarta saja
sudah tidak cukup, tentunya kebutuhan biaya hidup layak di kota besar lain khususnya
wilayah JABODETABEK tidak akan berbeda jauh dengan Jakarta. Di sisi lain, apabila peminjam
memiliki kemampuan secara finansial untuk melunasi utangnya, ini tidak semerta-merta
menjadi sebuah kabar baik. Secara tidak langsung, penghasilan peminjam yang lulus kuliah
sebagian besar akan digunakan untuk melunasi utang-utang mereka, sehingga tingkat
konsumsi rumah tangga keluarga (C) akan menurun. Hal ini menyebabkan, tingkat pendapatan
domestik bruto (Y) yang menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi pun akan menurun
pula, ceteris paribus.
Jika angsuran kredit pendidikan tidak mempengaruhi konsumsi, hal tersebut akan
mempengaruhi komponen pendukung rumah tangga lainnya, yaitu tabungan (S). Jika
kemampuan menabung masyarakat menurun, uang yang tersedia untuk investasi akan
berkurang (persamaan ekonomi dimana Saving = Investment, dengan asumsi current account
konstan). Berkurangnya investasi juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Pernah dicoba tetapi gagal
Student loan sendiri sebenarnya pernah diberlakukan oleh perbankan di Indonesia
dahulu. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menceritakan
pengalamannya dahulu yang sempat menikmati student loan di Indonesia. Saat menjadi
mahasiswa tahun 1985, ia menggunakan kredit mahasiswa Inoensia dari Bank Negara
Indonesia (BNI) untuk membantu membiayai pendidikan tingkat akhirnya. Pada saat itu, Ia
mengatakan tidak ada bunga saat pelunasannya, kredit harus dilunasi setelah bekerja selama
dua hingga tiga tahun, namun pada akhirnya program student loan ini terhenti karena banyak
mahasiswa yang tidak mampu membayar pinjaman. Skema yang dilakukan saat itu, apabila
mahasiswa tidak mampu membayar kredit pinjaman maka ijazahnya akan ditahan.
Kenyataannya pada waktu itu, skema penahanan ijazah ini tidak efektif karena pada saat itu
ijazah asli tidak terlalu diperlukan selama mahasiswa memiliki fotokopi ijazah dengan legalisir
yang sah.
Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti, Thailand dan Malaysia yang
memiliki sistem administrasi dengan tingkat GDP yang lebih tinggi dari Indonesia, memiliki
bunga modal yang lebih rendah dan pendapatan manusia yang kebih tinggi memiliki rasio
gagal bayar 53% dan 49%. Maka jika hal ini diterapkan di Indonesia, akan ada kemungkinan
rasio gagal bayar yang timbul melebihi rasio gagal bayar Malaysia dan Thailand sehingga
pemerintah harus bersiap untuk mengeluarkan dana yang sangat besar dikemudian hari untuk
menalangi rasio gagal bayar ini. Sehingga dapat disimpulan bahwa, dalam jangka pendek
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 20
sistem student loan akan meringankan beban untuk APBN namun untuk jangka panjang akan
memberatkan APBN.
Konten Pencerdasan Terkait Biaya Pendidikan
“Uang Kuliah (Tak)Tunggal”
Kementrian Kebijakan Nasional KM ITB 2018-2019
Pendidikan Berdasarkan Konstitusi
Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus
memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa: ”Setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan”. Kata “setiap” dalam pasal tersebut menyatakan
keseluruhan dari sesuatu, atau dalam hal ini merujuk pada istilah seluruh warga negara,
umumnya Warga Negara Indonesia, bukan hanya sebagian atau beberapa elemen warga
negara saja. Tidak hanya itu, komitmen bangsa Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan
tertuang pada tujuan negara (Alinea IV pembukaan UUD 1945) yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa yang menjadi penekanan bagi kita bersama bahwa pendidikan yang terakses adalah
hal esensial bagi kita masyarakat Indonesia. Kajian ini dikurasi ulang berdasarkan tulisan yang
dilansir oleh Ignatius Rhadite11.
Lebih lanjut perwujudan konstitusi negara Indonesia dalam hal mewujudkan
pendidikan yang terjangkau tertulis dalam pasal 6 (b) UU No 12 tahun 2012 (UU Pendidikan
Tinggi) bahwa pendidikan tinggi dilandasi dengan prinsip demokratis dan tidak diskriminatif,
tentu saja kaitannya dengan setiap insan yang berhak memperoleh dan mengenyam
pendidikan tinggi tersebut. Hal ini juga ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi
“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskrimanitf
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan
kemajemukan bangsa.”
Langkah Pemerintah untuk Mewujudkan Uang Kuliah Terjangkau
Sebelum diberlakukannya sistem Uang Kuliah Tunggal, masih segar di ingatan kita bahwa
biaya pendidikan tinggi tergolong mahal karena masih menarik uang pangkal untuk kuliah.
Namun hal tersebut berubah dengan diberlakukannya Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Sistem ini merupakan suatu upaya untuk mewujudkan biaya kuliah yang “murah” di seluruh
Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan sistem ini, mahasiswa sudah tidak akan dikenakan
11
https://suarr.id/menggugat-komersialisasi-pendidikan-indonesia-pendidikan-murah-kenapa-tidak/
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 21
biaya gedung, praktikum, uang SKS, uang wisuda, Uang Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau biaya
tambahan lainnya karena sudah dikumpulkan menjadi satu dalam UKT. Alasan
diberlakukannya UKT menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi adalah sebagai berikut:
1. Biaya SPMA atau Uang Pangkal yang selama itu berlaku dirasa memberatkan calon
mahasiswa
2. Biaya operaional yang selama ini dibutuhkan oleh PTN dalam proses Kegiatan Belajar
Mengajar dirasa tinggi sehingga “dibebankan” ke calon mahasiswa
3. Selain adanya uang pangkal, pada setiap semesternya mahasiswa diharuskan
membayarkan biaya diluar SPP untuk biaya operasional pendidikan
4. Terbatasnya kesempatan belajar di PTN bagi calon mahasiswa dari golongan kurang
mampu dan menengah dikarenakan tingginya biaya pendidikan.
Penindaklanjutan kebijakan ini diimplementasikan dengan Peraturan Menteri nomor 55
tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kemudian
disusul dengan terbitnya surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Nomor: 305/E/T/2012
tentang tarif uang kuliah dan surat nomor: 488/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah tunggal
yang meminta perguruan tinggi untuk:
1. Menghapus uang pangkal mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun
akademik 2013/2014.
2. Menetapkan dan melaksanakan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru
program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
Uang Pangkal menghilangkan Semangat Pendidikan Terjangkau Bagi Setiap Manusia
Uang Kuliah Tunggal menjadi sebuah harapan baru bagi setiap orang-orang di
Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara lebih terjangkau.
Namun, sejak tahun Tahun 2015 lalu, UU DIKTI beserta turunannya (Peraturan Menteri)
mengenai UKT masih menimbulkan persoalan bagi calon mahasiswa baru atau mahasiswa
umumnya. Sistem pembayaran uang kuliah tunggal yang melarang pungutan lain terhadap
mahasiswa diploma atau sarjana masih menyisakan celah.
Di dalam pasal 8 (Permenristekdikti) No. 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan
Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tiniggi Negeri menjelaskan;
“PTN dilarang memungut uang pangkal dan atau selain UKT kepada mahasiswa baru program
sarjana dan diploma”. Tapi kebijakan ini masih kontradiktif terhadap dirinya sendiri. Sebab di
dalam pasal 9 ayat 1 memberikan legitimasi bagi perguruan tinggi untuk melakukan pungutan
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 22
uang angkal atau sejenisnya kepada mahasiswa baik program diploma maupun sarjana. “PTN
dapat memungut uang pangkal dan atau pungutan lain selain UKT, dari mahasiswa baru
program sarjana dan program diploma yang terdiri atas; mahasiswa asing, mahasiswa klas
internasional, mahasiswa jalur kerjasama dan mahasiswa melalui seleksi jalur mandiri”
Celah ini menjadi sebuah pernyataan dari pemerintah melalui Permenristekdikti No. 39
tahun 2017 bahwa pemerintah membiarkan kampus memugut biaya pendidikan selain UKT.
Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 telah memasang standart gandanya. Kebijakan UKT
dianggap menjadi jaminan atas biaya pendidikan yang murah dan terjangkau bagi seluruh
mahasiswa baru dan terbebaskan dari pungutan lain, namun kenyataannya perguruan tinggi
juga masih diperbolehkan memungut biaya lain selain UKT. Maka menjadi pertanyaan bagi
kita semua, apakah pemerintah benar-benar memiliki keseriusan dalam menjamin biaya
pendidikan tinggi yang murah bagi masyarakat. Karena sejak UKT diamanatkan di dalam pasal
88 UU DIKTI untuk dijalankan, masih menuai protes di kalangan mahasiswa.
Berlanjut di tahun 2018 ini secara terang-terangan Uang Pangkal masih diberlakukan
di salah satu Universitas di Indonesia yakni di Universitas Negeri Semarang (Unnes). Pada awal
tahun 2018 uang pangkal mahasiswa diwajibkan untuk ditarik dalam jalur mandiri sebesar Rp
25 juta – Rp 40 juta12. Namun setelah mengalami protes dari mahasiswa, besara tersebut
berubah dari Rp 5 juta – Rp 25 juta sesuai golongan tanpa adanya pilihan 0 rupiah. Proses
penentuan besaran uang pangkal ini tidak melalui proses diskusi yang tranparan. Namun pihak
Universitas Negeri Semarang memberikan alasan bahwa pihak universitas berwenang menarik
uang pangkal karena diizinkan oleh Permenristekdikti No. 29 tahun 2017. Tanggapan terakhir
dari pihak Universitas Negeri Semarang kepada mahasiswa yang mengkritisi kebijakan uang
pangkal ini berbunyi demikian : ““Jika yang dituntut adalah hapus uang pangkal, maka
tuntutan ini salah sasaran karena yang mengeluarkan peraturan adalah Kemenristekdikti, kami
hanya menjalankan aturan sesuai Permenristekdikti,” 13
Benarkah Uang Kuliah benar-benar Tunggal?
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat celah dari kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang terjangkau, karena memberikan
kewenangan yang bebas kepada setiap PTN dalam memberlakukan uang pangkal. Tetapi
nyatanya celah permasalahan uang kuliah yang terjangkau berada pada penjaminan UKT itu
sendiri. Dengan adanya sistem UKT, harapannya biaya gedung, praktikum, uang SKS, uang
wisuda, Uang Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau biaya tambahan lainnya karena sudah
dikumpulkan menjadi satu dalam UKT tidak perlu ditarik kepada mahasiswa lagi. Tetapi dalam
keberjalanannya PTN masih saja menarik uang pungutan kepada mahasiswa.
12
https://radarsemarang.com/2018/06/05/tolak-uang-pangkal-hingga-rp-25-juta/
13
ibid
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 23
Bahwa untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkeadilan tentu perlu dijamin
dengan terciptanya kesetaraan akses bagi setiap anak bangsa. Jangan sampai harapan biaya
kuliah tunggal bagi mahasiswa justru kian memberatkan, apalagi mengarah kepana
komersialisasi yang sering kali kurang transparan seperti kenaikan yang signifikan, penentuan
golongan baru dan sebagainya. Oleh Karena itu menjadi penting untuk menjamin adanya
kepastian hukum baik dengan meninjau kembali permenristekdikti nomor 39 tahun 2017 yang
menjadi cikal bakal standar ganda pungutan dan juga membuka ruang demokratisasi kampus
yang menjamin hak-hak mahasiswa untuk ikut mengawasi arah pengembangan pendidikan
tinggi yang berkeadilan.
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 24
Kata Penutup
Pada akhirnya besar harapan kami untuk menjadi lilin-lilin kecil yang
merawat nyala semangat pendidikan yang mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagaimana yang diamanatkan para pendiri bangsa.
Buku ini kami susun bukan untuk berkata bahwa kami paling benar, tapi
kami percaya bahwa masih banyak pekerjaan kita bersama yang harus
terus kita perjuangkan, demi pendidikan berkeadilan.
Kami percaya bahwa tugas daripada pendidikan tinggi adalah untuk
menumbuhkan kemauan, menajamkan pikir, dan melembutkan hati.
Sehingga ruang-ruang kebebasan harus dijamin adanya, agar mekar
berbagai pemikiran, diskusi, dan inovasi.
Sedangkan kondisi di sentero negeri memberi kami kacamata, untuk
melihat realita lebih benderang. Pendidikan yang diidamkan masih jauh
dari cita-cita. Karena jangan sampai ada anak bangsa, yang tidak bisa
merubah hidupnya karena akses pendidikannya terhalang biaya.
Dan segala proses yang ada didalamnya, bukankah untuk mencetak
generasi yang sadar akan watak cendekia, mengenal kondisi bangsa
kemudian bergerak dan berkarya untuk kepentingan rakyat jelata.
Pantas kiranya bila kita semua bertanya, apa yang salah dengan
pendidikan tinggi kita?
Karena kampus harus bersih dari stigma untuk membangun kebebasan
berpikir dan siapa saja berhak untuk mendapat pendidikan yang layak
demi cerdasnya kehidupan bangsa.
Merdeka!
Kemenkoan Sosial Politik KM ITB 2018-2019 - 25
Anda mungkin juga menyukai
- OsteoarthritisDokumen3 halamanOsteoarthritisChandra ManapaBelum ada peringkat
- Laporan Kasus Bedah Orthopedi AnastasiaDokumen23 halamanLaporan Kasus Bedah Orthopedi AnastasiaChandra ManapaBelum ada peringkat
- 2016 Genap Peng PpdsDokumen8 halaman2016 Genap Peng PpdsAdi Sakti SetionegoroBelum ada peringkat
- Kasbes Anestesi NRBDokumen27 halamanKasbes Anestesi NRBChandra ManapaBelum ada peringkat
- Alat KKD Modul 5.2Dokumen4 halamanAlat KKD Modul 5.2Chandra ManapaBelum ada peringkat
- Journal Reading MataDokumen55 halamanJournal Reading MataChandra ManapaBelum ada peringkat
- Cluster HeadacheDokumen6 halamanCluster HeadacheChandra ManapaBelum ada peringkat
- Puskesmas Salaman II Terbaru BangetDokumen56 halamanPuskesmas Salaman II Terbaru BangetChandra ManapaBelum ada peringkat
- Rencana Kerja KelompokDokumen4 halamanRencana Kerja KelompokChandra ManapaBelum ada peringkat
- Puskesmas Salaman II Terbaru BangetDokumen56 halamanPuskesmas Salaman II Terbaru BangetChandra ManapaBelum ada peringkat
- Buku Saku Sabun Cuci Piring HerbalDokumen6 halamanBuku Saku Sabun Cuci Piring HerbalChandra ManapaBelum ada peringkat
- Sword Tab AkhirDokumen15 halamanSword Tab AkhirChandra ManapaBelum ada peringkat