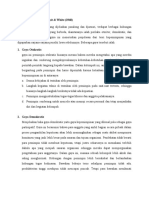HDHKNN
HDHKNN
Diunggah oleh
Muliani PaytreniJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
HDHKNN
HDHKNN
Diunggah oleh
Muliani PaytreniHak Cipta:
Format Tersedia
5
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Gagal Jantung
2.1.1. Definisi
Gagal jantung, secara klinis, didefinisikan sebagai suatu sindrom dengan
gejala yang khusus seperti sesak nafas, kelelahan, edema pre-tibial dan tanda
seperti peningkatan tekanan vena jugularis, ronki basah, dan displace apex beat
yang disebabkan oleh kelainan struktur dan fungsi jantung (European Society of
Cardiology, 2012).
2.1.2. Faktor risiko
Beberapa keadaan dapat berhubungan dengan kecenderungan terhadap
penyakit jantung struktural seperti usia, hipertensi, diabetes melitus, obesitas,
sindrom metabolik, penyakit jantung koroner, infark miokard, hipertropi ventrikel
kiri, anemia, kelainan jantung katup dan kardiomiopati.Yancy, et al. (2013)
menyebutkan hipertensi, diabetes melitus, sindrom metabolik, dan penyakit
aterosklerotik merupakan faktor risiko yang penting untuk gagal jantung.
Kejadian gagal jantung lebih sering pada pasien yang menderita hipertensi
kronis dan usia lanjut. Hipertensi dapat menjadi berkembang penyakit jantung dan
gagal jantung melalui dua cara, yaitu hipertrofi ventikel kiri dan penyakit jantung
koroner. Walaupun risiko gagal jantung karena hipertensi lebih sedikit
dibandingkan dengan penyakit jantung koroner, tetapi hipertensi lebih sering
ditemukan daripada miokard. Pengobatan hipertensi jangka panjang dapat
menurunkan risiko gagal jantung sekitar 50% (Mosterd dan Hoes, 2007;
Abrahamdan Hasan, 2007; Yancy, et al., 2013).
Pasien dengan diabetes melitus secara nyata meningkatkan kemungkinan
risiko untuk berkembang menjadi gagal jantung walaupun tanpa penyakit jantung
struktural sebelumnya. Diabetes mellitus juga mengganggu outcome dari tata
laksana gagal jantung (Yancy, et al., 2013).
Universitas Sumatera Utara
6
Pengobatan yang tepat untuk hipertensi, diabetes melitus dan dislipidemia
pada pasien sindroma metabolik dapat mengurangi risiko gagal jantung secara
signifikan (Yancy, et al., 2013).Pasien dengan penyakit aterosklerotik seperti pada
arteri koroner, serebral, dan pembuluh darah perifer, dapat berkembang menjadi
gagal jantung dan harus dikontrol risiko vaskularnya (Yancy, et al., 2013).Pada
penelitian yang dilakukan oleh Brouwers, et al. (2013), selama follow-up, gagal
jantung terjadi pada usia lebih tua, cenderung laki-laki dan memiliki BMI, tekanan
darah, dan denyut jantung yang tinggi, penurunan fungsi ginjal dan memiliki
faktor risiko kardiovaskular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan
hiperkolesterolemia.
2.1.3. Etiologi
Etiologi gagal jantung dapat dikelompokkan karena gangguan
kontraktilitas ventrikel, peningkatan afterload, dan gangguan relaksasi dan
pengisian ventrikel. Gagal jantung yang disebabkan karena gangguan
kontraktilitas ventrikel dan peningkatan afterload yang kronis disebut dengan
gagal jantung sistolik (gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi), sedangkan
gagal jantung yang disebakan karena gangguan relaksasi dan pengisian ventrikel
disebut dengan gagal jantung diastolik (gagal jantung tanpa penurunan fraksi
ejeksi) (Chatterjee dan Fifer, 2011).
Gangguan kontraktilitas ventrikel pada gagal jantung dengan penurunan
ejeksi fraksi dapat disebabkan oleh penyakit jantung koroner seperti infark
miokard atau iskemik miokard transient, volume overload yang kronis seperti
regurgitasi mitral atau regurgitasi aorta dan dilated cardiomyopathies. Sedangkan
gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi karena peningkatan afterload dapat
disebabkan oleh stenosis aorta yang sudah lanjut dan hipertensi yang tidak
terkontrol (Chatterjee dan Fifer, 2011).
Gagal jantung diastolik (gagal jantung tanpa penurunan ejeksi fraksi)
karena gangguan relaksasi dan pengisian ventrikel dapat disebabakan
olehhipertropi ventrikel kiri, restrictive cardiomyopathy, fibrosis miokard,
iskemik miokard transient, dan tamponade perikard (Chatterjee dan Fifer, 2011).
Universitas Sumatera Utara
7
Yancy, et al. (2013) menyebutkan beberapa penyebab gagal jantung karena
abnormalitas struktur jantung seperti dilated cardiomyopathies, familial
cardiomyopathies, kardiomiopati karena penyebab endokrin dan metabolik
(obesitas, diabetes, penyakit tiroid, akromegali dan insuffisiensi growth hormon),
toxic cardiomyopathy (alkoholik, kokain, terapi kanker), tachycardia-induced
cardiomyopathy, miokarditis dan kardiomiopati karena inflammasi (miokarditis,
AIDS, penyakit chagas), inflammation-induced cardiomyopathy (miokarditis
hipersensitivitas, reumatologik), kardiomiopati peripartum, kardiomiopati karena
kelebihan besi, amyloidosis, sarkoidosis jantung, stress (takotsubo)
cardiomyopathy. Menurut Cowie, et al. (1999) etiologi utama gagal jantung
disebabkan penyakit jantung koroner sebanyak 36%, tidak diketahui 34%,
hipertensi 14%, penyakit jantung katup 7%, fibrilasi atrium 5%, lain-lain 5%.
2.1.4. Patofisiologi
Beberapa mekanisme kompensasi terjadi pada penderita gagal jantung
untuk menanggulangi akibat dari penurunan curah jantung dan membantu
menjaga tekanan darah untuk perfusi ke organ vital (Triposkiadis, et al., 2009;
Chatterjee dan Fifer, 2011; Mann, 2012).
Mekanisme Frank-Starling merupakan salah satu kompensasi yang terjadi
pada jantung ketika ventrikel tidak mampu memompa secara adekuat, sehingga isi
sekuncup lebih rendah dari normal. Isi sekuncup yang rendah ini menyebabkan
volume yang tersisa setelah kontraksi jantung (end-systolic volume) menjadi lebih
banyak, sehingga darah yang akan berada di dalam ventrikel selama fase diastolik
akan lebih banyak. Volume yang tinggi pada fase diastolik ini menyebabkan
peningkatan regangan miofiber di jantung yang akan menginduksi kontraksi yang
lebih kuat, sehingga isi sekuncup lebih besar. Tetapi mekanisme ini tidak dapat
terpenuhi pada kasus gagal jantung yang sudah parah (Triposkiadis, et al., 2009;
Chatterjee dan Fifer, 2011; Mann, 2012).
Mekanisme neurohormonal juga teraktivasi sebagai kompensasi terhadap
penurunan fungsi miokard dan untuk menjaga homeostasis kardiovaskular.
Beberapa mekanisme neurohormonal ini adalah sistem saraf simpatis, sistem
Universitas Sumatera Utara
8
renin-angiotensin-aldosteron, sistem sitokin (Triposkiadis, et al., 2009; Chatterjee
dan Fifer, 2011; Mann, 2012).
Penurunan curah jantung yang terjadi pada gagal jantung akan
mengaktifkan sistem saraf simpatis. Regulasi sistem saraf simpatis ini diatur oleh
baroreseptor pada arcus aorticus dan sinus carotid, baroreseptor kardiopulmonari,
cardiovascular low-threshold polymodal receptor, dan peripheral
chemoreceptors. Ketika terjadi penurunan curah jantung, aktivitas baroreseptor
yang berada pada arcus aorticus dan sinus carotid berkurang terhadap curah
jantung, sehingga sinyal afferen yang dihantarkan melalui N.XII dan N.X ke
sistem saraf pusat pada pusat kardiovaskular di medulla oblongata berkurang.
Berkurangnya sinyal ini menyebabkan berkurangnya respon parasimpatis,
sehingga terjadi peningkatan respon simpatis seperti peningkatan denyut jantung,
penigkatan kontraktilitas jantung, penurunan kapasitas vena dan vasokonstriksi
pembuluh darah melalui stimulasi reseptor-α. Sinyal effren dari aktivasi respon
simpatis berjalan melalui saraf autonomik atau somatis (Triposkiadis, et al., 2009;
Chatterjee dan Fifer, 2011; Mann, 2012).
Peningkatan denyut jantung dan kontraktilitas oleh stimulasi reseptor β1-
adrenergik akan meningkatkan curah jantung. Vasokonstriksi vena akan
meningkatkan jumlah darah yang kembali ke jantung, sehingga memperbesar
preload dan peningkatan isi sekuncup melalui mekanisme Frank-Starling.
Vasokonstriksi arteri akan meningkatkan tahanan sirkulasi perifer, sehingga
mekanisme ini semua akan membantu menjaga tekanan darah untuk mempertahan
kan perfusi ke organ-oragan vital (Triposkiadis, et al., 2009; Chatterjee dan Fifer,
2011; Mann, 2012).
Selain mekanisme sistem saraf simpatis, sistem RAA juga diaktivasi
kemudian pada gagal jantung. Mekasnisme ini teraktivasi oleh karena beberapa
kondisi seperti: (1) hipoperfusi ginjal, (2) berkurangnya filtrasi natrium mencapai
macula densa pada tubulus distal, (3) stimulasi reseptor-β2 jukstaglomerulus
karena aktivasi sistem saraf simpatis. Sehingga akan menyebabkan peningkatan
sekresi renin dari sel jukstaglomerulus (Triposkiadis, et al., 2009; Chatterjee dan
Fifer, 2011; Mann, 2012).
Universitas Sumatera Utara
9
Renin berfungsi untuk memecah angiotensin menjadi angiotensin I (AngI),
yang kemudian akan dipecah lagi oleh angiotensin converting enzyme (ACE)
membentuk angiotensin II. Angiotensin II (AngII) merupakan vasokonstriktor
yang poten, sehingga meningkatkan tahanan sirkulasi perifer untuk
mempertahankan tekanan darah. AngII juga berperan dalam peningkatan tekanan
intravaskular dengan cara merangsang pusat haus di hipotalamus dan merangsang
korteks adrenal untuk meningkatkan sekresi aldosteron (Triposkiadis, et al., 2009;
Chatterjee dan Fifer, 2011; Mann, 2012).
Mekanisme kompensasi neurohormonal ini pada awalnya bermanfaat,
tetapi aktivasi jangka panjang mempunyai efek yang merusak terhadap struktur
dan kondisi jantung, sehingga memperburuk gagal jantung itu sendiri
(Triposkiadis, et al., 2009; Chatterjee dan Fifer, 2011; Mann, 2012).
Gambar 2.1. Mekanisme kompensasi neurohormonal (Mann, 2012)
2.1.5. Gejala dan tanda klinis
Dispnoea merupakan gejala yang paling jelas pada penderita gagal
jantung, terutama saat sedang melakukan kegiatan. Dispnoea terjadi karena
peningkatan tekanan vena pulmonari lebih dari 20 mmHg sehingga menyebakan
cairan bergeser ke jaringan interstisium paru dan kongesti parenkim paru. Hal ini
menyebabkan penurunan compliance paru, sehingga meningkatkan usaha
pernafasan. Penumpukan cairan ke interstitial juga akan menekan dinding
bronkiolus dan alveolus yang akan meningkatkan tahanan terhadap laju udara.
Universitas Sumatera Utara
10
Dispnoea juga dapat terjadi, walaupun tanpa ada kongesti di paru, karena
penurunan pasokan darah ke otot-otot respiratori dan juga penumpukan asam
laktat (Chatterjee dan Fifer, 2011).
Orthopnoea adalah sesak nafas yang dirasakan ketika penderita dalam
posisi berbaring dan membaik ketika duduk. Hal ini terjadi karena redistribusi
cairan intravaskular dari abdomen dan ekstremitas bawah menuju ke paru setelah
berbaring (Chatterjee dan Fifer, 2011).
Paroxysmal nocturnal dispnoea adalah sesak nafas yang terjadi ketika
penderita telah tertidur sekitar 2-3 jam. Gejala ini timbul karena reabsorbsi cairan
interstitial pada edema ekstremitas bawah ke dalam sirkulasi, sehingga
meningkatkan cairan intravaskular dan meningkatkan preload (Chatterjee dan
Fifer, 2011).
Gejala lain yang dapat dijumpai adalah seperti gangguan mental status
karena hipoperfusi ke jaringan otak. Gangguan produksi juga terjadi pada
penderita, seperti nocturia karena peningkatan perfusi darah ke ginjal ketika
berbaring. Periferal edema dan nyeri perut terjadi karena peningkatan tekanan
hidrostatik vena (Chatterjee dan Fifer, 2011).
Tanda klinis yang dapat dijumpai pada penderita gagal jantung adalah
seperti diaforesis, takikardia, takipnoea, ronki basah, S3 gallop, S4 gallop,
peningkatan tekanan vena jugularis, hepatomegali (Chatterjee dan Fifer, 2011).
Tabel 2.1. Gejala dan tanda klinis (McMurray, et al., 2012)
Gejala
Khas Kurang khas
Dispnoea Batuk malam hari
Orthopnoea Mengi
Paroxysmal nocturnal dispnoea Peningkatan berat badan (>2kg/minggu)
Penurunan berat badan (pada gagal
Toleransi aktivitas berkurang
jantung tingkat lanjut)
Lelah, letih Kembung
Edema pre-tibial Hilang nafsu makan
Kebingungan
Depresi
Palpitasi
Pingsan
Tanda
Spesifik Kurang Spesifik
Universitas Sumatera Utara
11
Peningkatan TVJ Edema perifer (tibial, sakral, skrotal)
Reflux hepatojugular Ronki basah
S3 gallop (irama gallop) Efusi pleura
Laterally displaced apical impulse Takikardia
Bising jantung Aritmia
Takipnoea (>16x/min)
Hepatomegali
Asites
Cachexia
2.1.6. Diagnosis
Diagnosis gagal jantung ditentukan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan
fisik dan pemeriksaan lain seperti ekokardiografi, elektrokardiografi, chest x-ray
dan pemeriksaan natriuretik peptida. Berdasarkan sistematik review yang
dilakukan oleh Jant, et al. (2009), banyak dari gejala dan tanda yang dapat muncul
pada pasien gagal jantung memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang bervariasi.
Misalnya dispnoea merupakan gejala yang hanya memiliki sensitivitas tinggi 87%
dibandingkan gejala dan tanda yang lain, tetapi hanya memiliki spesifisitas 51%.
Sedangkan gejala klinis yang lain memiliki spesifisitas yang tinggi, tetapi
sensitivitas yang rendah, seperti orthopnoea 89%, edema 72%, peningkatan
tekanan vena jugularis 70%, kardiomegali 85%, suara jantung tambahan 99%,
ronki basah 81%, dan hepatomegali 97%. Dengan sensitivitas masing-masing
44% (orthopnoea), 53% (edema), 52% (peningkatan TVJ), 27% (kardiomegali),
11% (suara jantung tambahan), 51% (ronki basah), 17% (hepatomegali). Selain
gejala klinis yang telah disebutkan, riwayat infark miokard juga memiliki
spesifisitas yang tinggi sekitar 89%, tetapi sensitivitas yang hanya 26%.
Elektrokardiografi digunakan untuk menentukan ritme jantung, denyut
jantung, morfologi dan durasi QRS dan kelainan lain yang dapat terdeteksi. EKG
juga digunakan untuk membantu dalam menentukan penatalaksanaan. EKG yang
normal dapat menyingkirkan kemungkinan gagal jantung sistolik (McMurray, et
al., 2012). Jant, et al. (2009) EKG memilikki sensitivitas yang tinggi sekitar 89%,
sedangkan spesifisitasnya hanya 56%.
Pemeriksaan B-type natriuretic peptides (BNP) juga memiliki sensitivitas
yang tinggi sekitar 93%, tetapi spesifisitas yang bervariasi. Peningkatan kadar
Universitas Sumatera Utara
12
BNP tidak dapat menegakkan diagnosis gagal jantung, tetapi kadar BNP yang
normal dapat menyingkirkan diagnosis gagal jantung. Pemeriksaan natriuretik
peptida lain seperti N-terminal pro-B-Natriuretic peptide (NT-proBNP) juga
memiliki sensitivitas yang tinggi 93% dan spesifisitas yang bervariasi, tetapi
spesifisitas yang lebih rendah daripada BNP (Jant, et al., 2009).
Chestx-ray memiliki spesifisitas sekitar 76-83% dan sensitivitas sekitar 67-
68%. Penemuan chest x-ray yang abnormal dapat membantu dalam menegakkan
diagnosis, tetapi chest x-ray yang normal tidak dapat menyingkirkan diagnosis
gagal jantung (Jant, et al., 2009).
Ekokardiografi merupakan alat diagnostik yang berguna dalam
mendiagnosis pasien gagal jantung. Ekokardiografi ini digunakan untuk menilai
struktur dan fungsi jantung, mengukur fraksi ejeksi, dalam mendiagnosis gagal
jantung dan penentuan penatalaksanaannya (McMurray, et al., 2012). Menurut
Jant, et al. (2009) pemeriksaan ekokardiografi harus segera dilakukan pada pasien
dengan gejala klinis yang dicurigai gagal jantung dan memiliki salah satu kondisi
sebagai berikut: Riwayat infark miokard, ronki basah, laki-laki dengan edema pre-
tibial.
2.1.7. Penatalaksanaan
2.1.7.1. ACE-inhibitor (angiotensin converting enzyme inhibitor)
Mekanisme :
Sistem renin-angiotensin berperan penting terhadap homeostasis
kardiovaskular. Efektor utama ini adalah angiotensin II (AngII), yang dibentuk
dari pemecahan Angiotensin I oleh ACE (angiotensin converting enzyme). ACE-i
menghambat perubahan AngI menjadi AngII, sehingga terjadi efek vasodilatasi
dan penurunan sekresi aldosteron. Efek vasodilatasi terjadi pada vena dan arteri,
sehingga akan menurunkan preload dan afterload yang akan mengurangi beban
jantung. Berkurangnya sekresi aldosteron akan menyebabkan terjadi ekskresi air
dan natrium yang juga akan mengurangi beban jantung. ACE-i juga menghambat
degradasi bradikinin, substansi P dan enfekalin. Bradikinin juga berperan terhadap
Universitas Sumatera Utara
13
efek vasodilatasi melalui stimulasi NO dan prostaglandin (Nafrialdi, 2009; Yamin,
et al., 2011).
ACE-i memiliki efek samping seperti, hipotensi, batuk kering,
hiperkalemia, edema angioneurotik, gagal ginjal akut, proteinuria dan efek
teratogenik. Kontraindikasi penggunaan ACE-i berupa riwayat angioedema,
stenosis arteri renalis bilateraldan hamil (Nafrialdi, 2009; McMurray, et al., 2012).
Efek antiremodelling:
Pembentukan AngII, sebagai respon dari stimulus patologi, berperan
penting dalam proses pengembangan hipertrofi jantung yang patologis. AngII
akan mengaktifkan GPCR (G-protein coupled receptor), yang akan menyebabkan
disosiasi Gαq. Aktivasi yang berlebih dari reseptor AngII AT1 dan Gαq akan
menyebabkan hipertrofi jantung pada hewan percobaan yang berhubungan dengan
perubahan ekspresi gen dan/atau disfungsi jantung dan kematian prematur
(McMullen dan Jennings, 2007).
AngII, di otak, akan menyebabkan feedback positif dengan cara
meningkatkan jumlah reseptor AngII AT1, inhibisi NO dan meningkatkan
produksi anion superoksida, sehingga akan meningkatkan laju simpatis dan
perburukan gagal jantung (Triposkiadis, et al., 2009).Efek AngII terhadap
perburukan gagal jantung (i.e remodelling jantung) itu sendiri akan dihambat oleh
ACE-i dengan mengurangi hipertrofi miokard dan penurunan preload (Setiawati
dan Nafrialdi, 2009).
2.1.7.2. ARB (angiotensin reseptor blocker)
Mekanisme:
ARB bekerja dengan cara menghambat reseptor AngII, sehingga akan
memberikan efek yang mirip dengan ACE-i. ARB tidak mempengaruhi
metabolisme bradikinin, sehingga tidak memiliki efek samping batuk kering dan
angioedema. ARB digunakan sebagai alternatif dari ACE-i(Nafrialdi, 2009).
Efek antiremodelling:
Universitas Sumatera Utara
14
Pada penelitian yang dilakukan oleh Aleksova (2012) terhadap ARB (i.e
candesartan) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap
fraksi ejeksi ventrikel kiri, penurunan diameter volumeend-diastolic ventrikel kiri,
penurunan kadar aldosteron, penurunan kadar B-natriuretic peptide.
2.1.7.3. Beta-blocker
Mekanisme:
Beta-blocker menghambat efek simpatis yang terjadi karena stimulasi
reseptor adrenergik-β. Stimulasi reseptor adrenergik-β1 akan meningkatkan denyut
jantung dan kontraktilitas jantung. Tetapi efek ini akan dihambat oleh beta-
blocker sehingga akan menurukan denyut jantung dan kontraktilitas jantung. Efek
ini juga akan mengurangi beban jantung dan oxygen demand. Beta-blocker juga
akan menghambat pelepasan renin, dan produksi AngII dan aldosteron, dengan
menghambat reseptor adrenergik-β1 yang ada pada sel jukstaglomerulus ginjal
(Lόpez-Sendόn, et al., 2004; Nafrialdi, 2009).
Beta-blocker juga memiliki efek samping seperti bradikardi yang
berlebihan, penurunan fungsi kontraksi ventrikel, bronkokonstriksi, memperburuk
kontrol diabetes, kelelahan dan kontraindikasi pada asma dan second- atau third-
degree AV block (Nafrialdi, 2009; McMurray, et al., 2012).
Efek antiremodelling:
disosiasi Gαq, yang berperan dalam proses hipertofi jantungseperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, juga dapat disebabkan oleh norepinefrin. Beberapa
literatur (Engelhardt, 2005; Setiawati dan Nafrialdi, 2009;Triposkiadis, et al.,
2009; van Berlo, 2013) juga menyatakan bahwa aktivasi berlebihan reseptor
adrenergik-β1 akan menyebabkan hipertrofi dan apoptosis ventrikel jantung.
Bersama dengan ACE-inhibitor/ARB, beta-blocker akan memberikan
efek antiremodelling. Beta-blocker juga dapat menurunkan angka kematian dan
meningkatkan fungsi sistolik jantung (Engelhardt, 2005; McMurray, et al., 2012).
2.1.7.4. MRA (mineralocorticoid receptor antagonist)
Universitas Sumatera Utara
15
Mekanisme:
MRA bekerja dengan cara menghambat reseptor aldosteron pada tubulus
colligens renalis kortikal dan bagian distal akhir, sehingga mencegah sekresi
K+(Ives, 2007).
MRA memiliki efek samping seperti ginekomastia, mastodinia, gangguan
menstruasi, gangguan libido pada pria dan kontraindikasi pada pasien dengan
hiperkalemia dan disfungsi ginjal (Nafrialdi, 2009).
Efek antiremodelling:
Spironolakton dapat mencegah remodelling matriks ekstraselular (Mann,
2012). Pada uji klinis terhadap pasien gagal jantung yang telah menerima ACE-I
dan diuretik, spironolakton dapat mengurangi angka mortalitas dan memperbaiki
gejala gagal jantung (Chatterjee dan Fifer, 2011). Eplerenon, MRA yang lebih
spesifik, telah menunjukkan peningkatan kelangsungan hidup pasien gagal
jantung yang telah infark miokard akut (Chatterjee dan Fifer, 2011).
2.1.7.5. Diuretik
Mekanisme:
Loop diuretic bekerja dengan menghambat simporter (kotransport) Na+-
K+-2Cl- dan menghambat resorpsi air dan elektrolit secara reversibel pada ansa
Henle asenden bagian epitel tebal. Tiazid bekerja dengan cara menghambat
transporter Na+-Cl- pada tubulus distal ginjal (Nafrialdi, 2009; Mann, 2012).
Efek samping loop diuretic dan thiazid adalah hipokalemia,
hiponatremia, hipomagnesemia dan hiperkalsemia (Nafrialdi, 2009).
2.1.7.6. Digitalis
Mekanisme:
Digitalis menghambat pompa Na+-K+-ATPase pada membran sel otot
jantung, sehingga meningkatkan kadar Na+ intrasel. Peningkatan ini akan
mengurangi pertukaran Na+-Ca+ selama repolarisasi dan relaksasi, sehingga Ca+
intrasel meningkat. Ca+ intrasel ini akan masuk ke dalam retikulum sarkoplasmik,
sehingga kadar Ca+ dalam retikulum sarkoplasmik akan meningkat. Jumlah Ca+
Universitas Sumatera Utara
16
yang banyak dalam retikulum sarkoplasmik ini akan menyebabkan kontraktilitas
jantung meningkat. Efek ini disebut inotropik positif (Setiawati dan Nafrialdi,
2009).
Dalam dosis terapi (1-2 ng/mL), digitalis akan meningkatkan tonus vagal
dan menurunkan aktivitas simpatis pada nodus SA dan AV. Hal ini akan
menimbulkan bradikardia sinus dan/atau perpanjangan konduksi AV bahkan
sampai blok AV. Efek ini disebut kronotropik negatif (Setiawati dan Nafrialdi,
2009).
Gambar 2.2. Algoritma tata laksana gagal jantung kronik (McMurray, et al., 2012)
Universitas Sumatera Utara
17
2.2. Pedoman Tata Laksana Gagal Jantung
Pedoman tata laksana merupakan ringkasan dan evaluasi dari semua
penelitian yang tersedia untuk membantu dokter dalam menentukan
penatalaksanaan yang terbaik untuk pasien, dengan mempertimbangkan dampak
dari outcome serta juga rasio risiko-manfaat sarana tata laksana tertentu
(McMurray, et al., 2012).
Sejumlah besar pedoman telah dikeluarkan oleh ESC dan juga beberapa
perkumpulan oraganisasi lain seperti ACCF/AHA (American College of
Cardiology Foundation/American Heart Association), HFSA (Heart Failure
Society of American), CCS (Canadian Cardiovascular Society), dan (ISHLT)
International Society for Heart and Lung Transplantation.
Penerapan pedoman tata laksana gagal jantung berpengaruh terhadap
outcome secara positif. Komajda, et al. (2005) menyebutkan bahwa kepatuhan
terhadap penerapan pedoman tata laksana gagal jantung menjadi prediktor yang
kuat terhadap kurangnya kejadian rawat inap. Penerapan farmakoterapi yang baik
berkaitan dengan prognosis yang lebih baik pada pasien gagal jantung dengan
penurunan fraksi ejeksi, terlepas dari umur dan jenis kelamin (Störk, et al., 2008).
Penerapan pedoman gagal jantung akut yang terdekompensasi menunjukkan
penurunan angka kematian, jangka waktu yang pendek, dalam tiga bulan (Braun,
et al., 2009). Richardson, et al. (2010) juga menyatakan penurunan angka
kematian pada usia lanjut dengan sebesar ≤ 6,1% dan angka kematian sekitar 20%
pada pasien tanpa pengobatan. Menurut Frankenstein, et al. (2010), peningkatan
penatalaksanaan berdasarkan pedoman tata laksana menurunkan angka kematian 1
tahun menjadi 14,1-4,8% antara tahun 1994-2000 dan 2001-2007, dan angka
kematian 3 tahun menjadi 29,5-10,9%.Zugck, et al.(2012) dalam penelitiannya
menyebutkan bahwa penerapan GAI-3 yang baik diprediksi memberikan
perubahan yang menguntungkan terhadap fraksi ejeksi ventrikel kiri dan diameter
end-diastolic diameter setelah 1 tahun.Pada penelitian yang dilakukan oleh Yoo,
et al. (2014) juga menyatakan bahwa penerapan pedoman tata laksana gagal
jatung berhubungan dengan outcome yang lebih baik.
Universitas Sumatera Utara
18
Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan itu juga, maka penerapan
pedoman tata laksana merupakan hal yang penting dalam penatalaksanaan
terhadap pasien gagal jantung. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk
mengetahui bagaimana penerapan pedoman tata laksana gagal jantung dalam
dunia klinis (Komajda, et al., 2005; Reibis, et al., 2006; Peters-Klimm, et al.,
2008; Erhardt, et al., 2008; Störk, et al., 2008; Braun, et al., 2009; Frankenstein, et
al., 2010; Maggioni, et al., 2010; Shoukat, et al., 2011; Zugck, et al., 2012;
Maggioni, et al., 2013; Maggioni, et al., 2013; Yoo, et al., 2014; Ajuluchukwu,
Anyika dan Raji, 2014).
Universitas Sumatera Utara
Anda mungkin juga menyukai
- Gaya Kepemimpinan Tannenbaum WarrentDokumen5 halamanGaya Kepemimpinan Tannenbaum WarrentMuliani PaytreniBelum ada peringkat
- Gaya Kepemimpinan LippitDokumen3 halamanGaya Kepemimpinan LippitMuliani PaytreniBelum ada peringkat
- BAB I Berfikir KritisDokumen18 halamanBAB I Berfikir KritisMuliani PaytreniBelum ada peringkat
- BAB III EditDokumen15 halamanBAB III EditMuliani PaytreniBelum ada peringkat