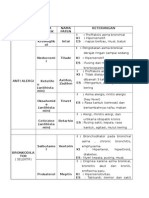Chapter II PDF
Chapter II PDF
Diunggah oleh
RSUD PABAJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Chapter II PDF
Chapter II PDF
Diunggah oleh
RSUD PABAHak Cipta:
Format Tersedia
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Diabetes Mellitus
2.1.1 Definisi Diabetes Mellitus
Menurut American Diabetes Association (ADA, 2003) dalam Soegondo
(2004), diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan
karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin
atau kedua-duanya.
Diabetes mellitus adalah sindrom yang disebabkan oleh ketidakseimbangan
antara kebutuhan dan suplai insulin. Sindrom ini ditandai oleh adanya hiperglikemia
dan berkaitan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak dan protein.
Istilah diabetes mellitus sebenarnya mencakup 4 kategori yaitu tipe 1 (insulin
dependent diabetes mellitus atau IDDM), tipe 2 (non insulin dependent diabetes
mellitus atau NIDDM), diabetes mellitus sekunder dan diabetes mellitus yang
berhubungan dengan nutrisi. Selain itu terdapat dua kategori lain tentang
abnormalitas metabolisme glukosa yaitu kerusakan toleransi glukosa (KTG) dan
diabetes mellitus gestasional (DMG) (Waspadji, 2007).
Diabetes mellitus tipe 1 mempunyai latar belakang kelainan berupa kurangnya
insulin secara absolut akibat proses autoimun, sedangkan diabetes mellitus tipe 2
mempunyai latar belakang resistensi insulin. Pada awalnya resistensi insulin belum
menyebabkan diabetes klinis. Sel beta pankreas masih dapat mengkompensasi,
Universitas Sumatera Utara
sehingga terjadi hiperinsulinemia, kadar glukosa darah masih normal atau sedikit
meningkat, selanjutnya terjadi kelelahan sel beta pankreas, baru terjadi diabetes tipe 2
yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (Waspadji, 2007).
Penderita diabetes mellitus tipe 2 mengalami penurunan sensitivitas terhadap
kadar glukosa, yang berakibat pada pembentukan kadar glukosa yang tinggi. Keadaan
ini disertai dengan ketidakmampuan otot dan jaringan lemak untuk meningkatkan
ambilan glukosa, sehingga mekanisme ini menyebabkan meningkatnya resistensi
insulin perifer (Perkeni, 2003).
Gejala klasik diabetes mellitus tipe 2 adalah adanya rasa haus yang
berlebihan, sering buang air kecil terutama di malam hari, dan berat badan turun
cepat, kadang-kadang ada keluhan lemah, kesemutan pada jari tangan dan kaki, cepat
lapar, gatal-gatal, penglihatan kabur, gairah seks menurun dan luka sukar sembuh
(Waspadji, 2007).
2.1.2 Epidemiologi Diabetes Mellitus
Diabetes mellitus tipe 2 meliputi lebih dari 90% dari semua populasi diabetes.
Prevalensi diabetes mellitus tipe 2 pada bangsa kulit putih berkisar antara 3-6% dari
orang dewasa.
Prevalensi diabetes mellitus tipe 2 dilaporkan lebih dari 40% adalah dewasa
dengan umur lebih dari 40 tahun, rata-rata prevalensi di Amerika Latin antara 15-41%
orang dewasa dengan umur lebih dari 45 tahun dengan gaya hidup barat dan sebesar
3% yang menderita diabetes mellitus tipe 2 dengan gaya hidup setempat. Prevalensi
umur 30-64 tahun di Pasific Island of Kiribati dan Samoa barat 11-16%, dan
Universitas Sumatera Utara
Melanesians Papua New Guinea 37% (The Diabetes Preventation Program Research
Group, 2003).
Prevalensi diabetes mellitus di Indonesia dilaporkan sebesar 6,15% di
Manado, Jakarta sebesar 12,8%, Jawa Barat sebesar 1,1%, dan Makasar sebesar 2,9%
(Soegondo, 2004).
Diabetes mellitus tipe 2 sangat sulit untuk ditanggulangi karena penyebab
terjadinya diabetes mellitus tipe 2 belum diketahui secara pasti, namun dari beberapa
penelitian diketahui beberapa faktor risiko yang meningkatkan kejadian diabetes
mellitus tipe 2 misalnya umur, riwayat keluarga, pola makan, obesitas, aktifitas fisik,
hiperlipidemia dan hipertensi (Rimbawan, 2004).
a. Agent (Bibit Penyakit)
Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh
masuknya agent tertentu dari luar tubuh penderita, melainkan karena disebabkan
oleh faktor individu itu sendiri. Beberapa teori tentang penyebab diabetes
mellitus tipe 2 telah diajukan tetapi belum ditemukan hasil yang memuaskan.
b. Host (Penjamu)
Beberapa pendapat menyebutkan adanya hubungan faktor individu yang
berpengaruh terhadap terjadinya diabetes mellitus tipe 2, antara lain umur,
hipertensi, obesitas, riwayat keluarga (Turtle, 1999).
1. Umur
Penelitian yang dilakukan CDC (Centre Disease Control and Preventation) di
Atlanta dari suatu survey epidemiologi bahwa prevalensi penderita diabetes
Universitas Sumatera Utara
mellitus diderita dewasa berumur 18 tahun sebesar 20% jika ada faktor riwayat
keluarga. Prevalensi diabetes mellitus pada umur 40 tahun meningkat menjadi
40%. Berdasarkan Perkeni (2003) DM diderita usia lebih dari 45 tahun, dan
semakin tingginya usia harapan hidup maka kemungkinan akan menderita
diabetes.
2. Hipertensi
Penelitian di Hongkong China (1997) oleh Chan, dilaporkan bahwa prevalensi
hipertensi meningkat dari kurang 5% pada orang normal menjadi 15-25% dengan
intoleransi glukosa. Hipertensi menyebabkan resistensi insulin, dislipidemia,
meningkatnya albuminuria dan pencatatan tekanan darah selama 24 jam dengan
orang yang menderita diabetes mellitus.
3. Obesitas
Obesitas adalah faktor risiko utama untuk diabetes mellitus. Berat badan yang
lebih dapat membuat dan menggunakan hormon insulin dengan baik. Diabetes
Program Prevention (DPP) menunjukkan bahwa berkurangnya berat badan dapat
membantu mengurangi risiko peningkatan diabetes mellitus karena hal itu akan
membantu hormon insulin yang digunakan oleh tubuh lebih efektif. Orang-orang
yang berat badannya turun antara 5-7% akan mengurangi risiko terkena diabetes
mellitus sebesar 58%.
Moore, et.al (2003) menunjukkan bahwa penurunan berat badan 3,7 – 6,8 kg
pada individu yang berusia 30-50 tahun mengurangi risiko diabetes mellitus
sebesar 33% dibandingkan dengan berat badan yang tetap gemuk. Hal ini
Universitas Sumatera Utara
menunjukkan faktor risiko obesitas merupakan faktor utama untuk terjadinya
penyakit diabetes mellitus.
4. Riwayat Keluarga
Pada banyak keluarga dan studi kembar, komponen yang besar dari faktor
genetik pada etiologi diabetes mellitus. Rata-rata penderita diabetes mellitus
dengan kembar monozygot sebesar 70-80%, kembar dizygot sebesar 10-20%.
Hal yang menarik tentang diabetes mellitus dari beberapa studi menunjukkan
bahwa ibu kandung yang menderita diabetes mellitus lebih menurunkan kepada
anak dari pada bapaknya yang menderita diabetes mellitus (The Diabetes
preventation Research Group, 2003).
c. Environment (Lingkungan)
Faktor lingkungan merupakan salah satu pemicu timbulnya diabetes mellitus.
Faktor lingkungan yang mempengaruhi adalah gaya hidup (lifestyle) yang terdiri
dari pola makan dan aktifitas fisik. Kedua faktor ini sangat berperan
menyebabkan tingginya kasus diabetes mellitus.
1. Pola Makan
Diet merupakan salah satu determinan penting penyebab obesitas dan
banyak hal penting dalam perkembangan diabetes mellitus. Suatu studi
historical menunjukkan diabetes mellitus diantara orang-orang yang terpapar
dengan makanan yang kurang dan makanan yang lebih pada populasi yang
banyak di Nauruans, dengan masukan kalori yang tinggi dan tingkat obesitas
Universitas Sumatera Utara
yang tinggi, mendukung hubungan yang signifikan untuk terjadinya diabetes
mellitus.
Heather, et.al., (2001) menunjukkan bahwa karbohidrat yang berbeda
akan memberikan efek berbeda pada kadar glukosa darah dan respon insulin,
walaupun diberikan dalam jumlah sama. Jumlah karbohidrat bukan dasar yang
cukup untuk mengendalikan kadar glukosa darah. Hasil penelitian bahwa
pangan dengan Index Glicemi rendah dapat memperbaiki pengendalian
metabolik pada penderita diabetes mellitus (Rimbawan, 2004).
2. Aktifitas Fisik
Penelitian yang dilakukan di USA pada 21.217 dokter selama lima
tahun menemukan bahwa kasus diabetes mellitus lebih tinggi pada kelompok
yang melakukan latihan jasmani kurang dari satu kali perminggu
dibandingkan dengan kelompok yang melakukan latihan jasmani lima kali
perminggu. Penelitian lain yang dilakukan selama delapan tahun pada 87.353
perawat wanita yang melakukan latihan jasmani ditemukan penurunan risiko
diabetes mellitus (The Diabetes preventation Research Group, 2003).
2.1.3 Patofisiologi dan Riwayat Alamiah Diabetes Mellitus Tipe 2
Glukosa yang diserap dari usus ke pembuluh darah dan diedarkan keseluruh
tubuh untuk dipergunakan oleh organ-organ dalam tubuh sebagai bahan bakar, supaya
dapat berfungsi glukosa harus masuk kedalam sel untuk di metabolisme yang
menghasilkan energi. Dalam proses metabolisme insulin memegang peranan sangat
Universitas Sumatera Utara
penting untuk memasukkan glukosa kedalam sel. Insulin adalah suatu zat atau
hormon yang dikeluarkan oleh sel beta pankreas.
Pada diabetes mellitus tipe 2 jumlah insulin normal, malah bisa lebih dari
normal tetapi jumlah reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel berkurang.
Glukosa yang masuk kedalam sel sedikit, maka sel akan kekurangan bahan bakar
(glukosa) dan glukosa dalam pembuluh darah meningkat. Berbeda dengan diabetes
mellitus tipe 1, pada awalnya diabetes mellitus tipe 2 disamping kadar glukosa darah
tinggi, juga kadar insulin tinggi atau normal, hal ini disebut dengan resistensi insulin.
Penyebab resistensi insulin tidak begitu jelas, tetapi ada faktor-faktor yang berperan
seperti obesitas, diet tinggi lemak dan rendah karbohidrat, kurang aktifitas fisik dan
faktor keturunan.
Secara alamiah diabetes mellitus tipe 2 berawal dari beberapa kombinasi
herediter dan faktor lingkungan menuju ke keadaan diabetes mellitus tipe 2 yang
menetap. Munculnya diabetes mellitus tipe 2 biasanya terjadi pada awal usia 18 tahun
atau lebih (Soegondo, 2004).
2.2 Komunikasi Petugas Pelayanan Informasi Obat (PIO)
2.2.1 Defenisi Komunikasi
Komunikasi berasal dari bahasa latin Communicare atau Communis yang
berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang
lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut
menjadi miliknya.
Universitas Sumatera Utara
Secara terminologis, menurut Nueman (2000) komunikasi diartikan sebagai
pemberitahuan sesuatu (pesan) dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan
suatu media. Sebagai makhluk sosial, manusia sering berkomunikasi satu sama lain.
Dalam kehidupan nyata mungkin ada yang menyampaikan pesan/ide; ada yang
menerima atau mendengarkan pesan; ada pesan itu sendiri; ada media dan tentu ada
respon berupa tanggapan terhadap pesan. Secara ideal, tujuan komunikasi bisa
menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang
disampaikan.
Menurut William (2004) dalam Yudistira (2009) manfaat yang dapat
diperoleh dengan berkomunikasi secara baik dan efektif diantaranya adalah :
1. Tersampaikannya gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas
sesuai dengan yang dimaksudkan.
2. Adanya kesepahaman antara komunikator dan komunikan dalam suatu
permasalahan, sehingga terhindar dari salah persepsi.
3. Menjaga hubungan baik dan silaturahmi dalam suatu persahabatan atau
komunitas.
Adapun unsur-unsur dalam komunikasi menurut Green (2000) antara lain :
1. Komunikator : pengirim (sender) yang mengirim pesan kepada komunikan
dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam
komunikasi karena merupakan awal (sumber) terjadinya suatu komunikasi
2. Komunikan : penerima (receiver) yang menerima pesan dari komunikator,
kemudian memahami, menerjemahkan dan akhirnya memberi respon.
Universitas Sumatera Utara
3. Media : saluran (chanel) yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai
sarana berkomunikasi. Berupa bahasa verbal maupun non verbal, wujudnya
berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi dan lain
sebagainya.
4. Pesan : isi komunikasi berupa pesan (message) yang disampaikan oleh
komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan
sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi
5. Tanggapan : merupakan dampak (effect) komunikasi sebagai respon atas
penerimaan pesan. Diimplementasikan dalam bentuk umpan balik (feed back)
atau tindakan sesuai pesan yang diterima.
Hewitt (2001) dalam Liliweri (2007), menjabarkan proses komunikasi secara
spesifik yaitu :
1. Mempelajari atau mengajarkan sesuatu
2. Mempengaruhi perilaku seseorang
3. Mengungkapkan perasaan
4. Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain
5. Berhubungan dengan orang lain
6. Menyelesaikan sebuah masalah
7. Mencapai sebuah tujuan
8. Menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik
9. Menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain
Universitas Sumatera Utara
Berikut ini diagram proses komunikasi menurut Liliweri (2007), terlihat pada
Gambar 2.1 :
Gangguan Gangguan
Balikan
Pengirim Penerima
pesan pesan
Simbol/Isyarat
Media (Saluran) Mengartikan
Kode/Pesan
Diagram 1 : Proses Komunikasi (Liliweri, 2007)
1. Pengirim pesan (sender) dan isi pesan/materi
Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada
seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan
sesuai dengan yang dimaksudkannya. Pesan adalah informasi yang akan
disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Pesan dapat verbal
(dilakukan secara langsung melalui tanya jawab, wawancara, sharing) atau
non verbal (melalui media poster, gambar, leaflet dan lainnya) dan pesan akan
lebih efektif (dapat lebih mudah diserap oleh penerima pesan) bila diorganisir
secara baik dan jelas melalui teknik dan metode yang dapat disesuaikan
dengan situasi dan kondisi audience (lingkungan tempat si penerima pesan
berada).
Materi pesan dapat berupa :
Universitas Sumatera Utara
a. Informasi
b. Ajakan
c. Rencana kerja
d. Pertanyaan dan sebagainya.
2. Simbol/isyarat
Pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya
dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya pengirim pesan menyampaikan
pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan (tangan,kepala,mata,
dan bagian muka lainnya). Tujuan penyampaian pesan adalah untuk
mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku atau menunjukkan arah
tertentu.
3. Media/penghubung
Adalah alat untuk penyampaian pesan seperti : TV, radio, surat kabar, papan
pengumuman, telepon dan lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi
oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi dsb.
4. Mengartikan kode/isyarat
Setelah pesan diterima melalui indera (telinga, mata dan seterusnya) maka
sipenerima pesan harus dapat mengartikan simbol/kode dari pesan tersebut,
sehingga dapat dimengerti/dipahaminya.
Universitas Sumatera Utara
5. Penerima pesan
Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari sipengirim
meskipun dalam bentuk kode/isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang
dimaksud oleh pengirim
6. Balikan (feedback)
Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari sipenerima pesan
dalam bentuk verbal maupun non verbal. Tanpa balikan seorang pengirim
pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Hal ini
penting bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima
dengan pemahaman yang benar dan tepat. Balikan dapat disampaikan oleh
penerima pesan atau orang lain yang bukan penerima pesan. Balikan yang
disampaikan oleh penerima pesan pada umumnya merupakan balikan
langsung yang mengandung pemahaman atas pesan tersebut dan sekaligus
merupakan apakah pesan itu akan dilaksanakan atau tidak balikan yang
diberikan oleh orang lain didapat dari pengamatan pemberi balikan terhadap
perilaku maupun ucapan penerima pesan. Pemberi balikan menggambarkan
perilaku penerima pesan sebagai reaksi dari pesan yang diterimanya. Balikan
bermanfaat untuk memberikan informasi, saran yang dapat menjadi bahan
pertimbangan dan membant menumbuhkan kepercayaan serta keterbukaan
diantara komunikan, juga balikan dapat memperjelas persepsi.
Universitas Sumatera Utara
7. Gangguan
Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi akan tetapi
mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi, karena pada setiap situasi
hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Gangguan adalah hal yang
merintangi atau menghambat komunikasi sehingga penerima salah
menafsirkan pesan yang diterimanya.
2.2.2 Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Informasi obat adalah setiap data atau pengetahuan objektif, diuraikan secara
ilmiah dan terdokumentasi mencakup farmakologi, toksikologi dan penggunaan
terapi dari obat. Informasi obat mencakup nama kimia, struktur kimia, identifikasi,
indikasi diagnostik atau indikasi terapi, ketersediaan hayati, bioekivalen, toksisitas,
mekanisme kerja, waktu mulai bekerja dan durasi obat, dosis dan jadwal pemberian,
dosis yang direkomendasikan, konsumsi, absorpsi, metabolisme, detoksifikasi,
ekskresi, efek samping, reaksi merugikan, kontraindikasi, interaksi, harga,
keuntungan, tanda, gejala, dan pengobatan toksisitas, efikasi klinik, data komparatif,
data klinik, data penggunaan obat, dan setiap informasi lain yang berguna dalam
diagnosis, dan pengobatan pasien dengan obat (Siregar,2004).
Menurut Santoso (1997), Informasi Obat adalah keterangan mengenai obat,
terutama yang dapat mendukung tercapainya tujuan pengobatan (terapi) yang tepat,
rasional, efisien dan aman dalam penggunaannya. Informasi yang diperlukan oleh
pasien, paling tidak mencakup dua hal yaitu : (1) Informasi mengenai jenis
penyakitnya dan pengobatannya, dan (2) Informasi mengenai obat yang diberikan
Universitas Sumatera Utara
padanya. Adapun hal-hal yang perlu diinformasikan kepada konsumen kesehatan
(pasien) terkait penggunaan obat antara lain : (a) Nama obat ( merek dagang ) dan
kegunaannya, (b) Tujuan dan manfaat terapi, (c) Cara penyediaan obatnya, (d) Dosis,
bentuk obat, rute pemberian dan lama pemberian, (e) Efek samping, interaksi dan aksi
obat, (f) Pantangan selama penggunaan obat, (g) Cara Penyimpanan obat, (h)
Informasi pengulangan obat, (i) Interaksi dan kontraindikasi, (j) Cara monitoring
terapi atau keberhasilan tercapai, (k) Tindakan terhadap persediaan obat yang tersisa
padahal sakit sudah dirasakan sembuh, (l) Tindakan apabila terjadi kesalahan dosis
maupun kesalahan makan obat, (m) Tindakan pencegahan dari jangkauan anak kecil.
Menurut SK Menkes RI No. 1197/MENKES/SK/X/2004, Pelayanan
Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker
untuk memberi informasi secara akurat, tidak bias dan terkini kepada dokter,
apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien.
Menurut Depkes RI (2004) kegiatan PIO meliputi : (1) Memberikan dan
menyebarkan informasi kepada pasien secara aktif dan pasif, (2) Menjawab
pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat atau tatap
muka, dan (3) Membuat bulletin, leaflet, dan label obat.
Menurut SK Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan RI No.
HK.01.DJ.II.093 tahun 2004 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Obat di Rumah
Sakit, tersedianya pedoman dalam rangka pelayanan informasi obat yang bermutu
dan berkesinambungan dalam rangka mendukung upaya penggunaan obat yang
Universitas Sumatera Utara
rasional di Rumah Sakit. Untuk itu diperlukan upaya penyediaan dan pemberian
informasi yang meliputi :
1. Lengkap, yaitu dapat memenuhi kebutuhan semua pihak sesuai dengan
lingkungan masing-masing rumah sakit.
2. Memiliki data cost effective obat, informasi yang diberikan terkaji dan tidak bias
komersial.
3. Disediakan secara berkelanjutan oleh institusi yang melembaga.
4. Disajikan selalu baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kefarmasian dan kesehatan.
Widayati dan Zairina (1996) menyatakan Apoteker merupakan tenaga ahli
dalam memberikan informasi tentang obat, baik kepada pasien maupun tenaga
kesehatan lain, dan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi
tersebut. Apoteker berkewajiban menjamin bahwa pasien memahami tujuan dari
pengobatan dan ketepatan penggunaannya, untuk itu apoteker perlu mengembangkan
tampilan dalam menyampaikan informasi agar pasien dapat mematuhinya. Pengertian
dan kerjasama pasien terhadap peraturan obat yang telah diresepkan merupakan
syarat penting untuk mencapai terapi yang efektif.
Juliantini dan Widayati (1996) menyatakan dalam memberikan PIO,
diperlukan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:
1. Permintaan Informasi Obat, meliputi : (a) mencatat data permintaan informasi, dan
(b) mengkategorikan permasalahan, antara lain : (1) aspek farmasetika (identifikasi
obat, perhitungan farmasi, stabilitas, dan toksisitas obat) (2)ketersediaan obat, (3)
Universitas Sumatera Utara
harga obat, (4) efek samping obat, (5) dosis obat, (6) interaksi obat, (7)
Farmakokinetik, (8) Farmakodinamik, (9) aspek farmakoterapi, dan (10)
keracunan.
2. Mengumpulkan latar belakang masalah yang ditanyakan, meliputi : (a)
menanyakan lebih dalam tentang karakteristik pasien, dan (b) menanyakan tentang
informasi yang diperoleh pasien sebelumnya.
3. Penelusuran sumber data, meliputi : (a) Dimulai dari rujukan umum (b) Disusul
dengan rujukan sekunder (c) Bila perlu diteruskan dengan rujukan primer.
4. Formulasikan jawaban sesuai dengan permintaan, meliputi : (a) Jawaban harus
jelas, lengkap dan benar, (b) Jawaban dapat dicari kembali pada rujukan asal, dan
(c) Tidak boleh memasukkan pendapat pribadi.
5. Pemantauan dan Tindak Lanjut, yakni menanyakan kembali kepada penanya
manfaat informasi yang telah diberikan baik lisan maupun tertulis.
Langkah-langkah sistematis tersebut dapat digambarkan pada gambar 2.2 berikut ini :
Universitas Sumatera Utara
Penanya
PIO
Isi Formulir
Klasifikasi
Penanya
Pertanyaan
Umpan
Informasi latar balik
belakang
Kumpulan data dan
evaluasi data
Formulir jawaban
Dokumentasi
Komunikasi
Gambar 2.2. Alur menjawab pertanyaan dalam pelayanan informasi obat
Sumber : Juliantini dan Widayati, 1996.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 2.2. Dapat dijelaskan bahwa penanya berada di ruang PIO, petugas
mengisi formulir mengenai klasifikasi, nama penanya dan pertanyaan yang
ditanyakan, setelah itu petugas menanyakan tentang informasi latar belakang penyakit
mulai muncul, petugas melakukan penelusuran sumber data dengan mengumpulkan
data yang ada kemudian data dievaluasi. Formulir jawaban didokumentasikan oleh
petugas lalu kemudian dikomunikasikan kepada penanya. Informasi yang
dikomunikasikan petugas kepada penanya akan menimbulkan umpan balik atau
respon penanya.
Menurut Depkes RI (2004), tujuan PIO adalah : (1) menyediakan informasi
mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit, (2)
menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan
dengan obat, terutama bagi panitia/Komite Farmasi dan Terapi (KFT), (3)
meningkatkan profesionalisme Apoteker, dan (4) menunjang terapi obat yang
rasional.
Siregar (2004) menyatakan sasaran informasi obat adalah orang, lembaga,
kelompok orang, kepanitian, dan penerima informasi obat tersebut, seperti tertera di
bawah ini :
1. Dokter, dalam proses penggunaan obat, pada tahap penetapan pilihan obat serta
regimennya untuk seorang pasien tertentu, dokter memerlukan informasi dari
apoteker agar ia dapat membuat keputusan yang rasional, yang bertujuan untuk :
(a) Menetapkan sasaran terapi dan titik akhir dari terapi obat, (b) Pemilihan zat
aktif terapi yang paling tepat untuk terapi obat yang bergantung pada variabel
Universitas Sumatera Utara
penderita dan zat aktif, (c) Penulisan regimen obat yang paling tepat, (d)
Pemantauan efek dari terapi obat didasarkan pada indeks dari efek, dan (e)
Pemilihan metode untuk pemberian obat. Dokter harus dibuat waspada terhadap
efek samping yang mungkin timbul, sifat distribusi obat dalam tubuh, dan efek
obat pada metabolisme. Dokter juga harus diberi informasi tentang stabilitas
suatu sediaan obat dan harga obat.
2. Perawat, dalam tahap penyampaian atau distribusi obat kepada perawat dalam
rangkaian proses penggunaan obat, apoteker memberikan informasi obat tentang
berbagai aspek obat pasien tertentu, terutama tentang pemberian obat. Sebagai
contoh tentang kompatibilitas atau inkompatibilitas tiga obat parenteral yang
perlu diberikan pada waktu yang sama kepada pasien dengan hanya satu
pembuluh (pipa) intravena. Perawat adalah juga profesional kesehatan yang
paling banyak berhubungan dengan pasien. Oleh karena itu, perawatlah pada
umumnya yang pertama mengamati reaksi obat merugikan atau mendengar
keluhan mereka. Apoteker harus siap berfungsi sebagai sumber utama informasi
obat bagi perawat. Berbagai hal yang dipertanyakan oleh perawat misalnya bahan
pengencer suatu rekonstitusi sediaan obat, gejala efek samping, kecepatan
timbulnya gejala efek samping dan penanganan/tindakan jika terjadi efek
samping.
3. Pasien, dalam tahap pemantauan efek obat serta tahap edukasi dan konseling
dalam rangkaian proses penggunaan obat, apoteker secara aktif memberikan
informasi kepada pasien.
Universitas Sumatera Utara
4. Tenaga Farmasi, agar apoteker mampu menjawab pertanyaan sendiri dan
bertindak sebagai sumber utama dari informasi obat bagi professional kesehatan
lain, tenaga farmasi harus mempunyai akses kepustakaan sebagai acuan yang
memadai dan pengetahuan tentang sumber alternatif dari informasi obat.
5. Pihak lain, seperti manajemen, tim/kepanitiaan klinik, dan lain-lain yang
berguna dalam penyusunan kebijakan – kebijakan di Rumah Sakit.
Menurut Rantucci (2007), PIO dengan berbagai macam bentuknya,
membawa dampak yang positif baik bagi apoteker maupun bagi pasien yang
bersangkutan. Bagi Apoteker PIO memberi manfaat berupa : (1) legal protection,
karena sudah melakukan kewajiban profesi Apoteker yang diatur oleh undang-
undang, (2) pemilihan status keprofesian, dimana keberadaan Apoteker akan lebih
diakui oleh masyarakat, (3) terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap Apoteker
sehingga dapat mewujudkan hubungan yang lebih harmonis antara Apoteker dengan
pasien, (4) meningkatkan pendapatan, karena tambahan pelayanan yang diberikan
berupa informasi obat, sehingga menjaga kepuasan pasien, dan (5) peningkatan
kepuasan kerja (job satisfaction) dan mengurangi stress (job stress).
Pasien juga mendapat manfaat dengan adanya PIO, yaitu : (1) mengurangi
resiko terjadinya kesalahan dan ketidakpatuhan pasien terhadap aturan pemakaian
obat, (2) mengurangi resiko terjadinya efek samping obat, dan (3) menambah
keyakinan akan efektivitas dan keamanan obat yang digunakan.
Rantucci (2007) menyatakan bahwa, ada banyak faktor yang harus
diperhatikan dalam memberikan pelayanan informasi kepada pasien. Faktor-faktor ini
Universitas Sumatera Utara
meliputi karakteristik pasien, jenis obat yang diresepkan atau kondisi penyakit yang
sedang diobati, dan berbagai aspek yang berkaitan dengan situasi. Selain itu, ada
beberapa faktor yang berkaitan dengan apoteker sendiri.
(1) Karakteristik Pasien, karakteristik pasien akan mempengaruhi penekanan yang
perlu diberikan pada aspek tertentu dalam konseling. Usia pasien dapat
mempengaruhi konseling dengan berbagai cara. Pasien manula mungkin
menggunakan beberapa macam obat untuk mengatasi beberapa kondisi penyakit
dan mungkin mengalami reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat sebagai
akibat dari perubahan fisiologis di usia yang semakin menua. Oleh karena itu
apoteker kemungkinan harus meluangkan lebih banyak waktu untuk pasien ini
dibandingkan untuk pasien lain dalam mengidentifikasi masalah, menjelaskan
petunjuk-petunjuk yang diperlukan, dan membantu pasien mengatur jadwal
dosis. Demikian juga, pasien pediatrik membutuhkan perhatian lebih dalam
mengidentifikasi masalah karena anak-anak memiliki kondisi fisiologis yang
berbeda dari orang dewasa. Latar belakang budaya pasien juga dapat
memengaruhi penekanan yang diberikan dalam konseling. Beberapa pasien
memiliki cacat tertentu yang memengaruhi pemilihan tempat yang tepat untuk
melaksanakan konseling, materi edukasi yang digunakan, dan jenis informasi
yang mungkin dibutuhkan. Jenis pekerjaan dan gaya hidup pasien kemungkinan
juga perlu diperhatikan. Bentuk sediaan, jadwal dosis, dan efek samping
kemungkinan perlu dimodifikasi dan pengaturan khusus mungkin perlu
dilakukan. Sebagai contoh pengemudi truk akan mendapat kesulitan bila minum
Universitas Sumatera Utara
obat yang membuatnya mengantuk. Jenis kelamin, status pekerjaan, atau situasi
sosial ekonomi pasien tidak seharusnya mengubah jenis konseling yang
diberikan; akan tetapi, faktor-faktor ini sebaiknya diperhitungkan oleh apoteker
saat melaksanakan suatu diskusi agar apoteker tidak membuat pasien malu atau
melukai hati pasien.
1. Karakteristik Obat, isi konseling bervariasi tergantung pada obat yang
didapatkan oleh pasien, apakah obat resep atau obat tanpa resep. Selain itu, obat
tertentu lebih cenderung menimbulkan masalah ketaatan penggunaan obat, efek
samping, atau tindakan pencegahan dibandingkan obat yang lain. Apoteker
harus memberi penekanan bila suatu obat diketahui beresiko tinggi mengalami
interaksi atau menimbulkan efek merugikan. Hal lain yang perlu
dipertimbangkan sehubungan dengan obat kemungkinan adalah waktu yang
diperlukan sampai pasien merasakan suatu efek, seperti pada obat
antihipertensi, dalam situasi seperti ini, hal yang penting dilakukan adalah
membantu pasien menemukan cara mengenali efek obat dengan tujuan
mendorong ketaatan pasien mengikuti pengobatan (misalnya, menyarankan
pasien mengecek sendiri tekanan darahnya).
3. Karakteristik Kondisi, kondisi tertentu kemungkinan lebih membangkitkan emosi
atau kekhawatiran pada pasien dibandingkan kondisi lain. Sebagai contoh,
diagnosis dan prognosis tekanan darah tinggi sering sulit dipahami. Demikian
juga, diagnosis gangguan psikiatri dapat membuat pasien merasa malu dan
cemas akan reaksi orang lain. Khususnya, bila sakit yang diderita pasien fatal,
Universitas Sumatera Utara
misalnya kanker atau AIDS, pasien akan memiliki berbagai kekhawatiran dan
emosi sehingga memerlukan perhatian khusus dari apoteker. Selain itu, sangat
penting menekankan bahwa obat bekerja untuk mengontrol atau mengurangi
gejala yang muncul dan bukan menyembuhkan penyakit, serta konsekuensi bila
terlewat minum obat. Beberapa kondisi lebih memerlukan adanya perubahan
gaya hidup pada pasien dibandingkan kondisi lain. Sebagai contoh, merokok,
kegemukan, atau diabetes memerlukan perubahan kebiasaan dan diet, Apoteker
perlu meluangkan waktu konseling yang cukup banyak untuk mendiskusikan
isu-isu ini, membuat rujukan bantuan lebih lanjut, dan memberikan konseling
lanjutan untuk terus mendukung pasien.
4. Karakteristik Situasi, situasi tertentu dapat menciptakan tantangan dan
membutuhkan penekanan yang berbeda dalam konseling. Situasi yang
menyebabkan pasien marah, ketakutan, atau kecewa secara emosional dapat
membuat konseling berjalan sangat sulit bagi apoteker. Selain itu, apoteker
sering dimintai konsultasi oleh pasien mengenai berbagai kekhawatiran yang
tidak berhubungan dengan terapi obat. Meskipun situasi tersebut tidak
memerlukan konseling pengobatan, namun apoteker harus menanggapi situasi
tersebut karena apoteker berkedudukan sebagai sumber daya kesehatan
masyarakat yang ada di komunitas dan sebagai individu yang mempedulikan
sesama manusia.
5. Karakteristik Pemberi Informasi (Apoteker), dalam pemberian informasi kepada
pasien (konseling), tidak saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari
Universitas Sumatera Utara
pasien melainkan juga yang berasal dari apoteker sendiri. Tingkat pengetahuan
apoteker tentang pasien (kekhawatiran, situasi keluarga, kondisi, dan gejala
pasien) menentukan pemahaman apoteker tentang cara mendekati pasien,
jumlah informasi yang perlu diberikan, dan kenyamanan apoteker dalam
menghadapi pasien. Pengetahuan apoteker tentang kondisi dan pengobatan
pasien yang dibicarakan dalam konseling juga penting karena apoteker harus
mampu mengantisipasi isu-isu yang harus dibicarakan dan memberikan
informasi yang diperlukan. Kemampuan Apoteker untuk berkomunikasi dengan
pasien dan profesional kesehatan lain yang terlibat dalam pengobatan pasien
juga sangat penting. Penggunaan empatilah yang terpenting dalam menghadapi
situasi yang menantang sehingga apoteker mampu menghadapi emosi pasien
seperti kemarahan, rasa malu, rasa takut, dan kebingungan yang umumnya
muncul dalam situasi seperti ini. Apoteker harus memiliki toleransi, empati, dan
ketertarikan pada masing-masing pasien. Hal ini akan dirasakan oleh pasien dan
akan membantu mengembangkan hubungan yang berhasil.
2.2.3 Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)
PKMRS adalah upaya penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan di rumah
sakit, yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman pasien dan keluarganya
tentang penyakit yang diderita pasien, serta hal-hal yang perlu dan dapat dilakukan
oleh keluarga, untuk membantu penyembuhan dan mencegah terulangnya kembali
penyakit yang diderita. Dalam hal ini PKMRS berusaha menggungah kesadaran serta
minat pasien dan keluarganya untuk berperan secara positif dalam penyembuhan dan
Universitas Sumatera Utara
pencegahan penyakit. Oleh karena itu penyuluhan kesehatan harus merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari upaya pelayanan kesehatan di RS, karena dengan PKMRS
upaya penyembuhan pasien akan lebih berhasil (Depkes RI, 1999).
Rumah Sakit mempunyai peran yang besar untuk menyebarkan informasi
kesehatan, pengembangan sikap dan perubahan perilaku kepada pasien, keluarga
pasien, masyarakat dilingkungan rumah sakit, dan juga kepada petugasnya.
A. Visi PKMRS
Mewujudkan ”rumah sehat” yang para warganya hidup dengan perilaku yang
bersih dan sehat, serta dalam lingkungan yang sehat pula.
B. MISI
1. Mengupayakan adanya kebijakan rumah sakit yang Bersih dan Sehat baik
warga, tampilan fisik rumah sakit, maupun lingkungan sekitarnya.
2. Mengembangkan iklim atau suasana kondusif bagi terselenggaranya
kegiatan penyuluhan di rumah sakit.
3. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk berperilaku
hidup bersih dan sehat bagi warga dan lingkungan rumah sakit.
C. KEBIJAKAN PKMRS
1. PKMRS difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat di rumah sakit
untuk hidup sehat dan mengembangkan lingkungan yang sehat.
2. PKMRS merupakan bagian dari program rumah sakit secara keseluruhan,
untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
Universitas Sumatera Utara
3. PKMRS dilakukan secara edukatif-persuasif, dan praktis-pragmatis,
dengan membuka jalur komunikasi, menyediakan informasi dan
melakukan edukasi (proses pembelajaran).
4. PKMRS dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat di rumah sakit secara
kemitraan dan berkesinambungan.
5. PKMRS dilakukan sesuai dengan perkembangan jaman, serta sesuai
dengan budaya dan kondisi setempat.
Adapun pesan atau materi PKMRS disesuaikan dengan masalah kesehatan
yang sedang diderita pasien atau penyakit terbanyak yang ditemukan di rumah sakit
(masalah lokal/SMF), atau masalah penyakit yang bersifat nasional (yang cenderung
meningkat secara nasional seperti : penyakit jantung, tekanan darah tinggi, TBC,
kanker, dsb) dengan aspek pencegahannya.
Secara garis besar, isi penyuluhan dapat dibagi menjadi 3 hal, yaitu :
1. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan individu maupun kelompok.
2. Mencegah terserang suatu penyakit atau penyakit yang diderita kambuh
kembali. Juga mencegah penularan penyakit kepada atau dari orang lain.
3. Membantu proses penyembuhan dan pemulihan.
Metode penyuluhan yang dapat dikembangkan dalam PKMRS dapat
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan langsung adalah
penyuluhan/komunikasi tanpa menggunakan alat perantara, dimana penyuluh
berbicara langsung kepada seseorang/sekelompok orang di hadapan penyuluh seperti:
tanya jawab perorangan, ceramah pada kelompok, dan konseling. Penyuluhan tidak
Universitas Sumatera Utara
langsung adalah penyuluhan/komunikasi melalui alat bantu atau media perantara
seperti : radio kaset, video kaset, flipchart, poster, booklet, leaflet, dan pameran.
Indikator keberhasilan PKMRS di lihat dari :
1. Adanya Tim pengelola PKMRS
2. Adanya kegiatan PKMRS yang berkesinambungan dan didukung oleh sumber
dana yang memadai
3. Adanya sarana dan media PKMRS yang memadai
4. Adanya peningkatan penampilan RS yang bersih dan sehat
5. Adanya peningkatan Perilaku Bersih dan Sehat dari petugas,
pasien/pengunjung.
2.3 Kepatuhan Pasien
Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti taat, suka menuruti, disiplin.
Kepatuhan menurut Trostle dalam Niven (2002), adalah tingkat prilaku penderita
dalam mengambil suatu tindakan pengobatan, misalnya dalam menentukan kebiasaan
hidup sehat dan ketetapan berobat. Dalam pengobatan, seseorang dikatakan tidak
patuh apabila orang tersebut melalaikan kewajibannya berobat, sehingga dapat
mengakibatkan terhalangnya kesembuhan.
Menurut Sacket (Niven, 2002) kepatuhan pasien adalah sejauhmana perilaku
pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh profesional kesehatan.
Menurut Sarafino (Bart, 1994) secara umum, ketidaktaatan meningkatkan
resiko berkembangnya masalah kesehatan atau memperpanjang, atau memperburuk
Universitas Sumatera Utara
kesakitan yang sedang diderita. Perkiraan yang ada menyatakan bahwa 20% jumlah
opname di rumah sakit merupakan akibat dari ketidaktaatan pasien terhadap aturan
pengobatan. Faktor yang memengaruhi kepatuhan seseorang dalam berobat yaitu
faktor petugas, faktor obat, dan faktor penderita. Karakteristik petugas yang
memengaruhi kepatuhan antara lain jenis petugas, tingkat pengetahuan, lamanya
bekerja, frekuensi penyuluhan yang dilakukan. Faktor obat yang memengaruhi
kepatuhan adalah pengobatan yang sulit dilakukan tidak menunjukkan kearah
penyembuhan, waktu yang lama, adanya efek samping obat. Faktor penderita yang
menyebabkan ketidakpatuhan adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, anggota
keluarga.
Faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan dapat digolongkan menjadi
empat bagian yaitu :
1. Pemahaman Tentang Informasi
Tak seorang pun mematuhi instruksi jika ia salah paham tentang instruksi
yang diberikan padanya. Ley dan Spelman (Niven, 2002) menemukan bahwa lebih
dari 60% yang diwawancarai setelah bertemu dengan dokter salah mengerti tentang
instruksi yang diberikan pada mereka. Hal ini disebabkan oleh kegagalan profesional
kesehatan dalam memberikan informasi yang lengkap, penggunaan istilah-istilah
medis, dan banyak memberikan instruksi yang harus diingat oleh pasien.
Pendekatan praktis untuk meningkatkan kepatuhan pasien ditemukan oleh
DiNicola dan DiMatteo (Niven, 2002) yaitu :
a. Buat instruksi tertulis yang jelas dan mudah diinterpretasikan.
Universitas Sumatera Utara
b. Berikan informasi tentang pengobatan sebelum menjelaskan hal-hal lain.
c. Jika seseorang diberikan suatu daftar tertulis tentang hal-hal yang harus diingat,
maka akan ada efek “keunggulan”, yaitu mereka berusaha mengingat hal-hal
yang pertama kali ditulis.
d. Instruksi-instruksi harus ditulis dengan bahasa umum (non medis) dan hal-hal
yang perlu ditekankan.
2. Kualitas Interaksi
Kualitas interaksi antara professional kesehatan dan pasien merupakan bagian
yang penting dalam menentukan derajat kepatuhan. Meningkatkan interaksi
professional kesehatan dengan pasien adalah suatu hal penting untuk memberikan
umpan balik pada pasien setelah memperoleh informasi tentang diagnosis. Pasien
membutuhkan penjelasan tentang kondisinya saat ini, apa penyebabnya dan apa yang
dapat mereka lakukan dengan kondisi seperti itu.
3. Isolasi Sosial dan Keluarga
Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan
keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga menentukan tentang program
pengobatan yang dapat mereka terima. Keluarga juga memberi dukungan dan
membuat keputusan mengenai perawatan dari anggota keluarga yang sakit.
4. Keyakinan, Sikap dan Kepribadian
Ahli psikologis telah menyelidiki tentang hubungan antara pengukuran-
pengukuran kepribadian dan kepatuhan. Mereka menemukan bahwa data kepribadian
secara benar dibedakan antara orang yang patuh dengan orang yang gagal. Orang-
Universitas Sumatera Utara
orang yang tidak patuh adalah orang-orang yang lebih mengalami depresi, ansietas,
sangat memerhatikan kesehatannya, memiliki kekuatan ego yang lebih lemah dan
yang kehidupan sosialnya lebih memusatkan perhatian pada dirinya sendiri.
Blumenthal et al (Niven, 2002) mengatakan bahwa ciri-ciri kepribadian yang
disebutkan diatas tersebut menyebabkan seseorang cenderung tidak patuh dari
program pengobatan.
Menurut teori Feuerstein dalam Niven (2002), ada lima faktor yang
mendukung kepatuhan pasien, dimana jika faktor ini lebih besar daripada
hambatannya maka kepatuhan harus mengikuti. Kelima faktor tersebut yaitu :
1. Pendidikan
Pendidikan pasien dapat meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa pendidikan
tersebut merupakan pendidikan yang aktif.
2. Akomodasi
Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian pasien yang dapat
memengaruhi kepatuhan. Sebagai contoh, pasien yang lebih mandiri harus dapat
merasakan bahwa ia dilibatkan secara aktif dalam program pengobatan, sementara
pasien yang lebih mengalami ansietas dalam menghadapi sesuatu, harus
diturunkan dahulu tingkat ansietasnya dengan cara meyakinkan dia atau dengan
teknik-teknik lain sehingga ia termotivasi untuk mengikuti anjuran pengobatan.
3. Modifikasi Faktor Lingkungan dan Sosial
Hal ini berarti membangun dukungan social dari keluarga dan teman-teman.
Kelompok pendukung dapat dibentuk untuk membantu kepatuhan terhadap
Universitas Sumatera Utara
program-program pengobatan seperti pengurangan berat badan, berhenti
merokok, dan menurunkan konsumsi alkohol.
4. Perubahan model terapi
Program-program pengobatan dapat dibuat sesederhana mungkin, dan pasien
terlibat aktif dalam pembuatan program tersebut. Dengan cara ini komponen-
komponen sederhana dalam program pengobatan dapat diperkuat, untuk
selanjutnya dapat mematuhi komponen-komponen yang lebih kompleks.
5. Meningkatkan Interaksi Profesional Kesehatan dengan Pasien
Adalah suatu hal yang penting untuk memberikan umpan balik pada pasien
setelah memperoleh informasi. Pasien membutuhkan penjelasan tentang
kondisinya, apa penyebabnya dan apa yang dapat mereka lakukan dengan kondisi
seperti itu. Konsultasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan.
Menurut Schwart dan Griffin (Bart, 1994), faktor yang berhubungan dengan
ketidaktaatan pasien didasarkan atas pandangan mengenai pasien sebagai penerima
nasihat dokter yang pasif dan patuh. Pasien yang tidak taat dipandang sebagai orang
yang lalai, dan masalahnya dianggap sebagai masalah kontrol. Riset berusaha untuk
mengidentifikasi kelompok-kelompok pasien yang tidak patuh berdasarkan kelas
sosio ekonomi, pendidikan, umur, dan jenis kelamin. Pendidikan pasien dapat
meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa pendidikan tersebut merupakan
pendidikan yang aktif seperti penggunaan buku-buku dan kaset oleh pasien secara
mandiri. Usaha-usaha ini sedikit berhasil, seorang dapat menjadi tidak taat kalau
situasinya memungkinkan. Teori-teori yang lebih baru menekankan faktor situasional
Universitas Sumatera Utara
dan pasien sebagai peserta yang aktif dalam proses pengobatannya. Perilaku ketaatan
sering diartikan sebagai usaha pasien untuk mengendalikan perilakunya, bahkan jika
hal tersebut bisa menimbulkan resiko mengenai kesehatannya.
Macam-macam faktor yang berkaitan dengan ketidaktaatan disebutkan :
1. Ciri-ciri kesakitan dan ciri-ciri pengobatan
Menurut Dickson dkk (Bart, 1994), perilaku ketaatan lebih rendah untuk
penyakit kronis (karena tidak ada akibat buruk yang segera dirasakan atau
resiko yang jelas), saran mengenai gaya hidup umum dan kebiasaan yang lama,
pengobatan yang kompleks, pengobatan dengan efek samping, dan perilaku
yang tidak pantas.
Menurut Sarafino (Bart, 1994), tingkat ketaatan rata-rata minum obat untuk
menyembuhkan kesakitan akut dengan pengobatan jangka pendek adalah sekitar
78%, untuk kesakitan kronis dengan cara pengobatan jangka panjang tingkat
tersebut menurun sampai 54%.
2. Komunikasi antara pasien dan petugas kesehatan
Berbagai aspek komunikasi antara pasien dengan petugas kesehatan
memengaruhi tingkat ketidaktaatan, misalnya informasi dengan pengawasan
yang kurang, ketidakpuasan terhadap aspek hubungan emosional dengan
petugas kesehatan, ketidakpuasan terhadap pengobatan yang diberikan
(Bart,1994).
3. Variabel-variabel sosial
Universitas Sumatera Utara
Hubungan antara dukungan sosial dengan ketaatan telah dipelajari. Secara
umum, orang-orang yang merasa mereka menerima penghiburan, perhatian, dan
pertolongan yang mereka butuhkan dari seseorang atau kelompok biasanya
cenderung lebih mudah mengikuti nasihat medis, daripada pasien yang kurang
mendapat dukungan sosial. Jelaslah bahwa keluarga memainkan peranan yang
sangat penting dalam pengelolaan medis. Misalnya, penggunaan pengaruh
normatif pada pasien, yang mungkin mengakibatkan efek yang memudahkan
atau menghambat perilaku ketaatan.
4. Ciri-ciri individual
Variabel-variabel demografis juga digunakan untuk meramalkan ketidaktaatan.
Sebagai contoh : di Amerika Serikat, kaum wanita, kaum kulit putih, dan orang
tua cenderung mengikuti anjuran dokter (Bart,1994).
2.4 Landasan Teori
Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit degeneratif yang
banyak diderita oleh penduduk dunia dan hingga saat ini belum ditemukan
pengobatan yang efektif untuk menyembuhkannya. (Depkes RI, 2006).
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Tahun 2004,
bahwa dari 14 juta orang menderita DM, 50% diantaranya sadar telah mengidapnya
(30% diantaranya yang mau berobat teratur dan 70% lainnya belum mengikuti
pengobatan secara teratur), selain itu masih ada 50% lainnya yang tidak menyadari
Universitas Sumatera Utara
dirinya menderita DM. Keadaan ini mencerminkan bahwa pemahaman masyarakat
tentang penyakit DM dan upaya pencegahannya masih rendah.
Kepatuhan yaitu tingkat/derajat dimana penderita DM mampu melaksanakan
cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh petugas kesehatan (Smet, 1994).
Shilinger (1983) yang dikutip Travis (1997) menyatakan bahwa kepatuhan mengacu
pada proses dimana penderita DM mampu mengasumsikan dan melaksanakan
beberapa tugas yang merupakan bagian dari sebuah regimen terapeutik. Trekas
(1984) dalam Ratanasuwan, dkk (2005), kemampuan penderita DM untuk
mengontrol kehidupannya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Seseorang yang
berorientasi pada kesehatan cenderung mengadopsi semua kebiasaan yang dapat
meningkatkan kesehatan dan menerima regimen yang akan memulihkan
kesehatannya.
Menurut teori Feuerstein dalam Niven (2002), ada lima faktor yang
mendukung kepatuhan pasien, yaitu pendidikan, akomodasi, modifikasi faktor
lingkungan dan sosial, perubahan model terapi dan meningkatnya interaksi
professional kesehatan dengan pasien.
Konseling dapat mengatasi ketidakpatuhan penderita DM. Edukasi yang baik
dan tepat akan menggugah kesadaran penderita untuk mau melaksanakan anjuran
kesehatan. Nicolucci et al (1996) dalam Day (2002) melaporkan bahwa penderita DM
yang tidak mendapatkan edukasi memiliki risiko 4 kali lebih tinggi terkena
komplikasi dibandingkan yang mendapatkan edukasi.
Universitas Sumatera Utara
Meningkatnya interaksi tenaga kesehatan melalui komunikasi dengan pasien,
adalah suatu hal penting untuk memberikan umpan balik pada pasien setelah
memperoleh informasi. Pasien membutuhkan penjelasan tentang kondisinya, apa
penyebabnya dan apa yang dapat mereka lakukan dengan kondisi seperti itu.
Informasi yang diperoleh pasien dapat membantu pasien untuk lebih memahami
kondisi mereka dan tindakan pengobatan yang sedang mereka jalani, dalam hal ini
cara penggunaan obat yang benar. Untuk meningkatkan interaksi tenaga kesehatan
dengan pasien, diperlukan suatu komunikasi yang terjalin baik oleh tenaga kesehatan.
Dengan komunikasi, seorang tenaga kesehatan dapat memberikan informasi yang
lengkap guna meningkatkan pemahaman pasien dalam setiap instruksi yang diberikan
kepadanya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam
menjalankan terapi (Niven, 2002).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Palestin (2000) pada pasien di poliklinik
penyakit dalam RSU.dr.Sardjito Yogyakarta menyatakan bahwa secara statistik
terdapat pengaruh yang bermakna setelah pemberian komunikasi terhadap kepatuhan
dalam pengobatan pada pasien diabetes mellitus. ( Palestin, 2002 ).
Pritchard (1989) menyatakan hubungan komunikasi dengan kepatuhan
merupakan variabel intermediet dari mengerti, kepuasan, dan memori. Membangun
suatu kepatuhan tergantung pada dua faktor disengaja atau tidak disengaja dan
biasanya didasari informasi yang benar harus selalu diberikan pada pasien yang tidak
patuh pada pelayanan medis yang mungkin secara langsung membantu mengingatkan
kembali. Sejak dia dipercaya dan patuh dengan nasehat, dia akan mengikuti
Universitas Sumatera Utara
pengalaman kesehatan masa lampau oleh karena perubahan perilaku memerlukan
banyak teknik persuasif (Palestin, 2002).
Menurut Smet (1994), salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan
adalah pemberian informasi, pemberian informasi yang jelas pada pasien dan
keluarga mengenai penyakit yang dideritanya serta cara pengobatannya. Dalam hal
ini pemberian informasi yang jelas tentang penggunaan obat secara benar, sehingga
pasien dapat paham dan akhirnya patuh terhadap anjuran pengobatan.
Ley dan Spelman (Niven, 2002) menemukan bahwa lebih dari 60% pasien
yang diwawancarai setelah bertemu dengan dokter salah mengerti tentang instruksi
yang diberikan pada mereka. Hal ini disebabkan oleh kegagalan profesional
kesehatan dalam memberikan informasi yang lengkap, penggunaan istilah-istilah
medis, dan banyak memberikan instruksi yang harus diingat oleh pasien.
Merujuk pada teori dan penelitian diatas dan berdasarkan survei pendahuluan
yang dilakukan peneliti terkait dengan kepatuhan pasien dalam konsumsi obat, maka
kajian komunikasi petugas informasi obat terhadap kepatuhan minum obat pasien
diabetes mellitus menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
2.5 Kerangka Konsep
Berdasarkan landasan teori tersebut di atas maka sebagai kerangka konsep
dalam penelitian ini dapat kita lihat dalam bagan dibawah ini :
Variabel Bebas Variabel Terikat
Komunikasi Petugas Pelayanan
Informasi Obat
Kepatuhan Minum Obat
1. Isi informasi
2. Metode informasi
3. Peran petugas
Gambar 2.3. Kerangka Konsep Penelitian
Universitas Sumatera Utara
Anda mungkin juga menyukai
- Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi Di Rumah SakitDokumen88 halamanPedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi Di Rumah Sakitarahma_688% (16)
- BijiDokumen4 halamanBijiOmiinkTryPapillioBelum ada peringkat
- Pembahasan Kimfar 4Dokumen3 halamanPembahasan Kimfar 4OmiinkTryPapillioBelum ada peringkat
- Denaturasi EnzimDokumen7 halamanDenaturasi EnzimOmiinkTryPapillio50% (2)
- FisikaDokumen234 halamanFisikaariratna16Belum ada peringkat
- Saluran PernafasanDokumen17 halamanSaluran PernafasanOmiinkTryPapillioBelum ada peringkat
- Karya Ilmiah Bahasa IndonesiaDokumen14 halamanKarya Ilmiah Bahasa IndonesiaOmiinkTryPapillioBelum ada peringkat