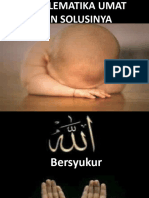Dalam Tulisan Ini
Dalam Tulisan Ini
Diunggah oleh
Maxwell0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
3 tayangan4 halamanJudul Asli
Dalam tulisan ini
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
3 tayangan4 halamanDalam Tulisan Ini
Dalam Tulisan Ini
Diunggah oleh
MaxwellHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 4
Dalam tulisan ini, penulis akan membahas apa saja nilai-nilai rancu yang terdapat dalam
Profil pelajar Pancasila, bagaimana Islam menjawab kerancuan tersebut.
Penulis berharap semoga dengan tulisan ini, pihak berwenang bisa mempertimbangkan
kembali bahwa Islam sebagai solusi ideal bagi setiap masalah. Islam menjadi solusi pembentukan
karakter bangsa dan umat manusia dan Islam pulalah satu-satunya sistem yang tepat dipakai dalam
bernegara.
II. Pembahasan
A. Nilai Rancu Profil Pelajar Pancasila
1. Pengejawantahan Islam dan Budaya
Indonesia adalah negara yang kaya akan budayanya, memiliki kepulauan terbesar di dunia
dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Banyak wisatawan tertarik dengan
budaya yang dimiliki Indonesia. Budaya menjadi salah satu aspek yang membanggakan bagi
masyarakatnya. Jika warga mancanegara mendengar kata ‘Indonesia’, pasti yang langsung teringat
dalam benak mereka adalah tentang kekayaan budaya dan keragaman yang ada di Indonesia.
Dengan kebanggaan tersebut, sangat disayangkan jika kebudayaan yang sedemikian banyak
hilang begitu saja. Mereka khawatir akan hilangnya keberagaman budaya yang ada Mari kita
mencoba mengilustrasikannya! Sebutkan harta yang paling anda cintai! Lalu, coba bayangkan jika
salah satu harta yang paling anda cintai itu tiba-tiba hilang begitu saja. Apa yang Anda rasakan? Pasti
anda akan merasakan kerisauan yang sanga mendalam. Dengan alasan itu pulalah, pemerintah
berupaya melakukan berbagai cara agar budaya Indonesia yang kaya dan beragam ini tak hilang dan
punah begitu saja.
Pengaburan budaya dan karakter bangsa menjadi salah satu kekhawatiran nasional saat ini.
Masalah yang telah terlampau lama mengenai budaya membuat pemerintah memutuskan menjadikan
pembentukan masyarakat berbudaya menjadi Rencana Pembangunan jangka panjang 2005-2025
Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan
meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan
pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya
interaksi antarbudaya. Namun, di sisi lain upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia,
seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan
rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Hal tersebut, disebabkan antara lain, karena
belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para
pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang
negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter
bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 1
Di era kepresidenan tahun 2020-2024, penguatan karakter bangsa ini juga dimasukkan ke
dalam Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045 dengan
dikeluarkannya Permendikbud RI Nomor 22 tahun 2020. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024
adalah:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk
mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya
Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan
YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global 2
Di lingkup Kementrian Pendidikan, upaya pemerintah dalam mempertahankan kekayaan
budaya Indonesia yaitu dengan dibuatnya Program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 6.
2
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020, Rencana Strategis Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan 2020-2024, Jakarta: Kemendikbud, hlm. 32
terletak pada dimensi berkebhinekaan global. Sebagaimana yang termaktub pada dokumen resmi
milik Kemendikbudristek sebagai berikut:
Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap
berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling
menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan
dengan budaya luhur bangsa.3
Dengan program ini, diharapkan pelajar Indonesia memiliki rasa cinta tanah air dan rasa
nasionalisme yang tinggi, apalagi di era disruptif saat ini. Era dimana berbagai budaya keluar dan
masuk silih berganti. Hal demikian dapat mengakibatkan budaya luhur menjadi ditinggalkan dan
tergantikan.
Di lingkup Kementrian Agama, Rencana Pembangunan ini diwujudkan dengan
pengimplementasiannya dalam pendidikan Islam. Kementrian Agama (Kemenag) meluncurkan
sebuah program yang mengajak pelajar untuk akomodatif terhadap budaya lokal.
Latar belakang upaya akomodatif terhadap budaya lokal dijelaskan di dalam buku yang
diterbitkan oleh Kemenag (Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam). Mereka
beralasan bahwa perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang
perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. 4
Buku ini juga menjelaskan bahwa hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu
yang ambivalen. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak
turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup
manusia.5
Mereka menganggap peleraian ketegangan antara dua hal ini (yaitu agama dan budaya) dapat
selesai dengan dijembatani oleh sejumlah kaidah-kaidah fiqih dan ushul fiqh. Mereka menjelaskan
kaidah seperti al- ‘âdah muhakkamah (tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum) yang diklaim
terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Dalil ini
dijadikan sebuah alasan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis yang bisa
menyesuaikan dengan ruang dan zaman.6
Pendapat itu dikuatkan juga dengan adanya berbagai upaya pribumisasi Islam, sebagaimana
yang dilakukan oleh para wali songo dahulu. Fakta tentang adanya usaha “Pribumisasi Islam”
merupakan jejak peninggalan dan warisan dakwah generasi awal pembawa Islam seperti Wali Songo
yang masih terlihat sampai hari ini dalam bentuk penyesuaian ajaran Islam semisal penggunaan
bahasa lokal sebagai ganti dari bahasa Arab. Sejumlah bahasa lokal yang digunakan untuk
menggantikan istilah berbahasa Arab, misalnya dalam penggunaan sebutan Gusti Kang Murbeng
Dumadi sebagai ganti dari Allah rabb al- ‘âlamîn, kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad
ammad saw., susuhunan atau sunan untuk menyebut hadrat al-shaikh, puasa untuk mengganti istilah
shaum, sembahyang sebagai ganti shalat, dan masih banyak lainnya. 7
Konsep Pribumisasi Islam adalah upaya pengejawantahan ajaran-ajaran Islam agar tidak
bertentangan dangan tradisi dan kebudayaan lokal. Mari kita simak salah satu kutipan yang diambil
dari buku Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam berikut:
3
Kepala Badan Standar, kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 009 /H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum
Merdeka, hlm.9.
4
Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Implementasi Moderasi
Beragama dalam Pendidikan Islam, Jakarta Pusat: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm. 21.
5
Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Implementasi Moderasi
Beragama dalam Pendidikan Islam, hlm. 21
6
Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Implementasi Moderasi
Beragama dalam Pendidikan Islam, hlm. 21
7
Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Implementasi Moderasi
Beragama dalam Pendidikan Islam, hlm. 23
Dalam konsep pribumi Islam ini (Jurnal Tashwirul Afkar: 2003) pengejawantahan ajaran-
ajaran Islam agar tidak bertentangan dangan tradisi dan kebudayaan lokal. Pribumisasi bukan
berarti meninggalkan norma-norma keislaman demi budaya, tetapi agar norma-norma tersebut
menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan
oleh variasi pemahaman nash (Al-Quran dan Hadis). Perpaduan di antara keduanya menjadi
saling melengkapi, di mana Islam lahir dari perintah Allah swt., sedangkan budaya merupakan
hasil dari kreasi manusia. Dalam pribumisasi Islam nampak bagaimana Islam diakomodasikan
ke dalam tradisi dan budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-
masing, sehingga tidak ada pemurnian Islam atau penyeragaman praktik keagamaan dengan
budaya Timur Tengah.8
Sikap keagamaan yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya di dalam lingkup
Kemenag dianggap merupakan bentuk yang kurang bijaksana. Tidak seharusnya dipertentangkan
antara keduanya dalam bentuk dualisme yang saling menjaga jarak, melainkan antara agama dan
budaya, keduanya saling mengisi. Konsep pemahaman keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi
dan budaya tersebut sejalan dengan konsep Islam.
Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal dapat
digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman tersebut bersedia untuk menerima praktik
keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Dengan program ini diharapkan lahir
orang-orang yang memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal
dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pemahaman
keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang
tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga
paradigma kontekstualis yang positif.
2. Keterbukaan: Antara Toleransi dan Kebebasan
Toleransi bukan hanya menjadi problem satu kelompok masyarakat atau budaya tertentu, tapi
menjadi problem kemanusiaan secara universal. Toleransi bukan menjadi problem di zaman sekarang
saja, melainkan sudah menjadi problem di zaman klasik, pertengahan hingga kontemporer. Di tengah
situasi masyarakat yang plural, rentan konflik dan fanatik golongan, dibutuhkan terobosan yang
mendukung gagasan toleransi.
Indonesia secara realitas merupakan negara yang plural. Kondisi ini membuat masyarakat
Indonesia rentan mengalami konflik dengan kelompok atau budaya lain. Pada 12 Mei 1998, terjadi
sebuah konflik terhadap etnis Tionghoa. Peristiwa tersebut berawal dari peristiwa penembakan empat
mahasiswa Trisakti yang terlibat demonstrasi untuk melenserkan Soeharto sebagi presiden RI.
Kejadian tersebut berbuntut panjang dan menyulut emosi warga. Akibatnya, keesokan harinya kisruh
aksi massa terjadi di beberapa titik. Penjarahan dan pembakaran pun tak dapat dihindarkan. Krisis
moneter berkepanjangan di tahun 1998 berujung pada aksi kerusuhan hebat pada penghujung rezim
Orde Baru. Kerusuhan tersebut menular pada konflik antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Selama
ini, etnis Tionghoa di Indonesia dianggap sebagai kelompok minoritas yang kaya dan sukses secara
ekonomi. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang merasa iri dan cemburu terhadap keberhasilan
mereka. Terdapat isu diskriminasi dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Tionghoa,
seperti diskriminasi dalam penerimaan di sekolah dan pekerjaan. Banyak toko dan rumah milik etnis
Tionghoa yang dirusak dan dibakar, serta banyak orang Tionghoa yang menjadi korban kekerasan dan
pemerkosaan. Kerusuhan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara ekonomi
maupun sosial.
Konflik tragis berbau agama juga turut meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan
pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999, telah berkembang menjadi
8
Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Implementasi Moderasi
Beragama dalam Pendidikan Islam, hlm. 22
aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan
bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam
dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang meregang nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini
saling serang dan bakar membakar bangunan serta sarana ibadah.
Tragedi Sampit, konflik berdarah antar suku yang paling membekas bagi bangsa Indonesia
pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak
faktor, di antaranya kasus orang Dayak yang didiuga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus
pemerkosaan gadis Dayak. Warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap gagal beradaptasi
dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini ratusan orang dikabarkan
meninggal dunia. Bahkan banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang
kalap dengan ulah warga Madura saat itu. Pemenggalan kepala itu terpaksa dilakukan oleh suku
Dayak demi memertahankan wilayah mereka yang waktu itu mulai dikuasai warga Madura.
Tak hanya konflik antar golongan saja, serangan-serangan dari teroris juga ikut mengancam
keamanan Indonesia. Dengan dalih agama, mereka melancarkan aksinya tersebut. Pemahaman yang
minim tentang agama membuat mereka tak paham arti dari kata perjuangan dan malah melakukan
perbuatan yang nekat serta membahayakan orang lain. Pengeboman yang terjadi di beberapa daerah
nyatanya justru semakin memperkeruh suasana toleransi antara umat beragama. Pemerintah juga
mendorong masyarakat untuk meningkatkan toleransi mereka dalam mengahadapi berbagai
permasalahan diatas.
Anda mungkin juga menyukai
- Materi 12.pptx'Dokumen24 halamanMateri 12.pptx'MaxwellBelum ada peringkat
- Materi 11.pptx'Dokumen56 halamanMateri 11.pptx'MaxwellBelum ada peringkat
- ينهض الإنسان بما عنده من فكرDokumen4 halamanينهض الإنسان بما عنده من فكرMaxwellBelum ada peringkat
- Materi 8.pptx'Dokumen32 halamanMateri 8.pptx'MaxwellBelum ada peringkat
- Meskipun Agama Lain Harus Diyakini Sesat Dan KufurDokumen8 halamanMeskipun Agama Lain Harus Diyakini Sesat Dan KufurMaxwellBelum ada peringkat
- Semangat Toleransi Terus Digaungkan Dari Tahun Ke TahunDokumen5 halamanSemangat Toleransi Terus Digaungkan Dari Tahun Ke TahunMaxwellBelum ada peringkat
- WswsDokumen3 halamanWswsMaxwellBelum ada peringkat
- Peran Orang Tua Mendidik Anak ADHDDokumen2 halamanPeran Orang Tua Mendidik Anak ADHDMaxwellBelum ada peringkat