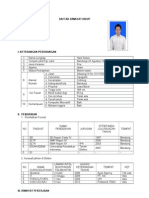Dua Kelamin Karmin
Diunggah oleh
Hadi SubariHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Dua Kelamin Karmin
Diunggah oleh
Hadi SubariHak Cipta:
Format Tersedia
Dua Kelamin Karmin Cerpen : Hadi Subari Ibu melenguh saat motor memepet di depan mobil, membunyikan suara
klakson beberapa kali setelah mengrem mendadak. Maaf membangunkanmu! Ujar Ibu sambil melirik ke sebelah kiri kursi belakang. Tidak, Bu. Saya sudah bangun dari tadi, sambil menahan rasa sakit di tenggorokan. Ibu mengambil posisi semula yang sempat terpelanting ke depan. saya pun begitu. Membaringkan tubuh di atas kursi mobil setengah terlentang tidak membuat rasa mual ini hilang. Euhh, Bu...? Saya urung bertanya. Ibu lekas menjawab, Ya, Mata kami berpapasan di cermin depan mobil. Saya menggelengkan kepala dan menahan nyeri pada bekas jaitan luka di kepala dengan tangan. Istirahat saja! Perintah Ibu. Saya pun menolehkan muka ke badan jalan. Perjalanan pulang dari rumah sakit berlangsung alot. Mobil-mobil saling membuntuti satu sama lain terutama di persimpangan lampu merah. Mungkin hari ini akhir pekan. Ah... lebih enak bila naik sepeda motor, jika boleh memaksakan kondisi. Bisa berkelok-kelok dan mengambil jalan jatah pejalan kaki. Ibu bercerita sekarang sudah memasuki musim hujan. Jika tiba-tiba turun hujan di tengah perjalanan, siapa yang repot, kata Ibu. Ibu memang tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Benar sekali. Hujan mengandung petir datang bersama Ibu menyambut saya di depan rumah sakit. Hujan masih juga belum berhenti ketika motor tadi berulah. Got-got memuntahi badan jalan. Muntahan air hitam itu mencuat-cuat seperti lumpuh hitam pekat. Plastik berbagai merek ikut promosi bergantian keluar bersama muntahan. Beruntung sebelum pergi saya minum obat antimuntah, jika tidak, saya sudah ikut-ikutan sepertinya. Mobil melaju kembali dan berhenti lagi, begitu seterusnya. Endapan butir-butir air di permukaan kaca mulai menyuram. Saya menyapunya dengan punggung tangan. Muntahan air hitam perlahan-lahan menyurut dan muncul kembali dengan semburat kemerah-merahan mencuat tak beraturan. Warnanya merah semerah darah berpancuran seperti keluar dari garis luka yang dalam. Dalam jaraknya, seorang pria kurus terkapar. Kepalanya sobek mengeluarkan darah. Pria lebih besar darinya berlari susah payah dari kejauhan. Berusaha menahan celana Levis-nya agar tidak melorot lalu menghampiri pria kurus itu. Memeriksa dengan seksama. Dia membalikan wajah pria yang terkapar tadi, wajahnya geram seketika lantas berdiri. Berdengus. Pria besar tadi mengambil kuda-kuda, mendorong pria kurus dengan kaki kanan sekuatnya. Pria kurus tadi tenggelam ke dalam selokan yang penuh darah. Aku menggosok-gosok permukaan kaca buram kembali. Aku berhalusinasi lagi. Tiba-tiba saya terhentak ke atas hampir menyundul bagian dalam atap mobil. Saya melirik dan memutarkan badan melihat jauh ke belakang dengan cepat. Mobil baru saja melewati polisi tidur, berbelok beberapa kali di atas jalan yang lebih kecil lalu sampailah di sebuah gerbang besi yang cukup tinggi. Sebuah rumah tua tak begitu jauh dari pintu gerbang besi barusan. Tubuh menjadi dingin mendadak menusuk sampai tulang. Garis hitam memenuhi hampir semua bagian rumah. Pohon-pohon besar berderet menjadi latar di belakang rumah. Sangat mencekam. Ibu bersegera masuk ke dalam rumah. Tak lama
kemudian, seorang pria berkulit terang, berkaos putih polos dan bercelana pendek keluar dari rumah. Dia mengeluarkan payung besar dan membukakan pintu mobil. Dia meraih ketiak ketika saya hendak menginjak tanah. Kulitnya berbulu penuh sepanjang tangan ketika saya meraihnya. Pegangannya kokoh. Ternyata wajahnya lebih terang bila dilihat dari dekat. Dia menuntun pelan, terlihat gugup dan hati-hati di atas tanah basah dengan udara begitu dingin. Kami menuju sebuah kamar setelah melewati ruang tamu, dapur dan beberapa pintu lainnya. Seprai putih dan tirai putih mencocok mata terlebih dahulu sebelum: lemari, meja rias, lampu tua, pintu melamin dan jajaran buku-buku. Pria terang tadi masih juga membantu meniduri dan menyelimuti tubuh yang masih lemah ini. Bisa kau panggilkan Ibuku? Saya tak pernah bertemu pria ini sebelumnya. Rasanya tanpa menyebut nama, hilang rasa hormat itu. Maka tak ku sebut pula namanya. Dan tak bermaksud merendahkan namun dia tersenyum manis dan lantas pergi. Mata ini makin lemah dan ibu tak juga tiba. Saya mendadak bangkit membuka mata dengan rasa sakit kepala luar biasa. Mendenyut beberapa kali lantas hilang begitu saja. Sekeliling ruang kamar gelap namun perlahan saya dapat melihat samar bentuk-bentuk benda di dalamnya. Pegangan pintu besi berhasil saya raih. Lampu menyala otomatis di koridor rumah tua ini. Membuat mataku perih. Perasaan lega mencuat karena saya bisa melihat dapur dengan jelas. Tenggorokan kering membuat diri bergegas menuju dapur. Itu salah Bapaknya! Suara nyaring berhasil menebus dinding sampai ke telingaku. Saya yakin itu suara Ibu. Dengan cepat sekali, dua gelas air putih berhasil masuk memenuhi perut. Saya kembali ke koridor tepat pertama kali saya keluar kamar. Mencari asal suara. Saya pun berdiri terdiam. Celangak-celunguk. Suara ibu tak terdengar lagi. Yang ada hanya suara ranting pohon menggaruk atap rumah dan suara burung hantu (barangkali). Tak diduga ternyata rumah ini begitu luas memanjang. Padahal tampak muka tadi sore, rumah ini kecil: pintu, beberapa kotak jendela dan satu set kursi kayu menghiasinya. Mengapa Ibu membawa saya ke rumah yang sangat aneh. Di tepi cahaya, saya melihat pintu kamar lain. Saya mulai bergerak kembali perlahan untuk menggapainya. Tak! Jatung saya berguncang. Penerangan di belakang mati tiba-tiba dan penerangan di depan muncul secara berbarengan. Saya pun sampai pada pintu yang tadi dilihat. Dan terlihat lagi, pintu kamar serupa di depan. Dan pintu kamar saya hanya terlihat samar. Gila! Rumah apa ini? Ada berapa kamar serupa di sepanjang koridor ini? Ada tiga atau mungkin lebih. Tubuh saya mulai bergetar tak karuan, jari-jari tangan rasanya mati, kaki gemeretak dan nafas mulai terasak. Lalu jatuh perlahan pada dinding koridor mengambil posisi duduk selonjoran. Lama kemudian saya bangkit berdiri sendiri menumpu pada benjolan dinding. Urung niat saya mencari Ibu atau menelusuri rumah tua ini. Tiba-tiba ada yang mengganjal dalam perut saya, seperti ingin buang air kecil. Saya pun kembali ke dalam kamar, berjalan cepat masuk ke kamar mandi. Udara dingin selalu meninggalkan jejak-jejak pada benda yang sepi. Menemaninya dengan titik-titik air di atas cermin. Saya duduk di atas porselen duduk setelah melorotkan celana biru. AkhhHHH... IBUUUUUUU! Saya memekik dan menangis sejatinya. Berdiri lalu membanting tutup porselen duduk. Menyambar gayung dan melemparkannya ke arah cermin. Cermin retak. Peretakan cekung cermin melingkar dan bergaris-garis.
Di setiap retakan memantulkan seribu wajah. Saya tak mengenali salah satunya. Saya memekik kembali, IBUUUU! Saya yang tak terbiasa mengunci pintu kamar mandi, membuat Ibu dapat dengan mudah membukanya. Dengan raut wajah aneh dan suara garau Ibu bertanya, Ada apa ini? Emosi saya meluap tak tahu arah. Ibu yang melihat air mata saya jatuh, langsung mendekap saya dan ikut menangis. Seperti tahu rasa sakit hati dan pendustaan ini, Ibu berkata Sabar ya, Kaka!, sambil mengeluselus punggung. Namun saya membuang pelukan Ibu. Di hadapan Ibu, saya menengadahkan kedua tangan dan memelas, Mana kelamin saya, Bu? **** Menjelang sore, dua minggu sebelum peristiwa di atas. Setelah pulang dari tugas pagi di Rumah sakit Jiwa tempat dia berkerja sebagai suster kepala, Mimin tak mendapati anaknya di rumah. Seperti biasa, Mimin mengecek ke pintu kulkas untuk melihat catatan kecil yang dibuat anaknya. Kertas kotak kuning bertulisan, Berenang dulu ya, Bu! I love u, menempel di sudut dekat buah-buahan bermagnet. Mimin pun pergi mandi dengan tenang, menghilangkan keringat lelah kemudian memasak untuk keperluan makan malam berdua bersama anaknya. Setelah selesai membuat makanan untuk makan malam, kebetulan langit senja telah berubah menjadi gelap gempita. Mimin mulai cemas menunggu kepulangan anaknya. Dia pun duduk di ruang tengah sambil melihat jam di dinding. Sungguh ajaib. Waktu berjalan lebih lambat ketika seseorang mulai mengamatinya. Dan itu membuatnya makin gelisah. Di hentak-hentakanlah kedua kakinya beriringan. Kaka tidak pernah pulang terlambat dan langsung belajar untuk besok! gerutunya. Pintu rumahnya pun akhirnya diketuk. Wajah yang sangat akrab dengannya berdiri gelisah di mulut pintu. Nafas orang itu masih tersengal-sengal seperti sudah lari marathon di sebuah lapangan tembak. Oh... Hendra! Mimin celingukan ke segala arah, Mana Karmin? Anu... Tante! Anu..., Hendra tak berani menatap wajah Ibu sahabatnya seperti biasanya. Anu... anu apa? Mimin makin gelisah dibuatnya. Kar... min jatuh... Tante, Hendra gelagapan. Jatuh bagaimana? Mimin menaikan nada suaranya dan mengayunkan tubuh Hendra berkali-kali, Jatuh dimana? Jatuh dekat kolam renang, Tante, Jawab Hendra meringkik. Mendengar itu, Mimin langsung masuk ke dalam menyambar jaket dan tas meninggalkan Hendra yang mulai lemas. Hendra mulai mengisi pikirannya dengan semua hal yang akan terjadi. Keringat mulai bertambah di punggungnya bukan keringat panas tadi habis berlari ke rumah temannya, melainkan keringat
dingin. Hendra terperanjat. Mimin kembali untuk bertanya sambil menepuk hendra dari belakang, Di mana Karmin sekarang? Mimin menuju rumah sakit tempat dimana dia pernah berkerja. Setelah menanyakan nama dan waktu kejadian pada pihak resepsionis, dia pun bergegas menuju kamar operasi. Seorang pria berambut putih sedang duduk di bangku. Pria itu mengenakan kaos putih dan celana panjang berbahan tahan air. Mimin lantas bersalaman dengan pria tersebut. Terima kasih, pak. Mimin menyalami kedua tangan pria itu. Saya Ibunya Karmin! Mimin pun terseyum getir. Saya guru olahraganya. Panggil saja Joko. Joko menyambut kedua tangan dingin Mimin yang halus. Bagaimana keadaan Karmin sekarang? Mimin yang cemas sepanjang perjalanan belum pula tenang dalam pertanyaannya. Ketika saya berlari menemukannya beberapa meter di jalan kecil sepanjang kali..., Mimin lantas memotong ucapan Joko, Dekat kali! Bukan jatuh dari kolam? Mimin melipatkan keningnya. Bukan. Jawab Joko lantas meneruskan perkataan yang sempat dipotong, Karmin sudah tak sadarkan diri. Kepalanya sobek. Mungkin terkena kawat pembatas. Dan darah sudah melumuri semua wajahnya. Saya pikir dia kena peras. Soalnya rawan daerah situ jika berjalan sendirian. Dan wajahnya biru-biru kena tinju. Bukan dia bersama Hendra? Tanya Mimin penasaran. Mungkin...! Jawab Joko tak yakin. Kok, mungkin sih, Pak? Tanya Mimin sedikit keras. Ya, saya juga kurang yakin. Tapi memang Hendra-lah yang berlari kepada saya memberitahukan keadaan Karmin, waktu saya bergerak pulang dari kolam renang. Banting Joko menjawab. **** Mimin memangku kepalanya dengan kedua tangan. Posisinya tak berubah semenjak Pak Joko telah pamit pulang. Dia mencoba bersabar atas kejadian nahas yang menimpa anaknya. Kejadian seperti ini bukan pertama kali baginya. Batinnya selalu digerus rasa nyeri untuk anaknya yang satu ini. Ketika mengetahui anak lelaki ketiganya berbeda dari kedua anak lelaki lainnya, Mimin mencoba terima takdir. Perbedaan itu pun mimin simpan rapat dari suaminya yang sering pergi berlayar. Dan ketika suaminya mengetahui rahasia yang disimpannya begitu rapat, suaminya pun tak sungkan-sungkan meninggalkannya begitu saja. Berdua bersama anak terakhirnya. Setidaknya Karmin tak kehilangan nyawa. Itu yang menjadi penenang dalam batinnya kini. Pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter yang sangat familier membuat keduanya tersenyum mersa. Mimin langsung mendekap hangat dokter itu. Suster-suster muda yang baru saja keluar keheranan. Dan langsung berlalu sambil berbisik diantara mereka.
Lama tak bertemu, Minah! Dokter Fadli membuka pembicaraan dengan menyebutkan nama kecil Mimin. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Minah mengalihkan pembicaraan. Dokter Fadli tersadar dari sebuah kenangan. Lalu dengan cepat menarik udara penuh ke dalam paru-paru dan menjawab gugup, Kita harus mengoperasi kelaminnya. Secepatnya! Mimin bagai mendengar guntur tepat di atas kepalanya. Tak ada alternatif lain, Adli? Mimin ber tanya mengunakan nama kecil dokter Fadli agar dia mampu memberikan jawaban yang lebih rasional yang dapat mengelus lembut ke dalam hati Mimin. Hujan pun selalu datang beriringan bersama guntur dan petir. Benar saja. Sebelum dokter Fadli menjawab, Mimin terlebih dahulu melihat Hendra beserta ibunya di meja resepsionis. Bagai kilatan cahaya. Mimin menyambar Hendra dan menamparnya keras sekali. Saking kerasnya hendra pun terjatuh ke lantai. Setiap orang yang melihat ini pasti akan memerah mukanya. Ketika Mimin ingin menerjang kembali Hendra yang ketakutan di lantai dengan kedua tangannya. Ibunya Hendra menghalau dan menenangkan Mimin. Mimin pun ambruk ke lantai dan menangis keras-keras. Awan hitam dihatinya perlahan berkurang. Setelah selesai berenang. Kami semua pergi ke ruang ganti. Pada mulanya semua berjalan seperti biasanya. Tak ada yang ganjil. Karena antrian sudah berjajar penuh di muka kamar kecil menunggu giliran. Seseorang pun mengusulkan untuk masuk berdua ke kamar mandi. Saat itu pula Karmin panik. Entah kenapa?! Dia pun langsung merangkul bahu saya. Saya tak masalahkan itu. Saya dan Karmin berteman sejak lama. Hendra mengawali cerita ketika Ibunya berhasil menenangkan Mimin yang hampir ngamuk di lantai rumah sakit. Hendra pun mulai tenang dan kembali meneruskan ceritanya. Karmin yang mulai gelisah. Kaki kanannya tak mau berhenti. Itu membuat semua teman memperhatikannya. Sebagian memincingkan mata, yang lainnya mengkerutkan dahi. Sadar dia menjadi pusat perhatian. Karmin pun menghentikan kaki dan melepaskan pegangan tangannya di lengan saya. Lalu tiba giliran kita masuk. Ketika di dalam kamar mandi, Karmin mengambil jarak dan buru-buru memunggungi saya. Dia melepaskan celana pendek lalu jongkok. Air hangat keluar membuat asap tipis dalam ruang kecil itu. Saya pun tahu Kamin sedang buang air kecil. Tapi kenapa berjongkok? Setelah selesai berganti baju dan tiba di mulut pintu kamar mandi. Bayu teman satu sekolah yang sering mengganggu dan memeras teman lainya berteriak keras. Dan teriakan itu tidak patut didengar oleh semua orang di ruang ganti tersebut. Berteriak apa? Mimin menimpali. Pasangan ho..., Hendra melirik Ibunya dan urung melanjutkannya. Maksud... kamu! Pasangan sejenis. Paksa Mimin. Hendra pun mengangguk. Kami tidak peduli hal itu. Toh... semua teman pun tahu saya punya pacar perempuan. Dan Karmin punya..., Hendra kembali gugup dengan menelan ludah. Tak ada satu pertanyaan pun keluar dari mulut ibu-ibu yang sedang memandangnya dengan seksama. Dia pun mengalihkan ceritanya. Itu pun karena diantara mereka tidak ada yang sadar akan hal itu.
Sebelum pulang kami makan terlebih dulu. Namun Karmin memilih makan di pojok dekat teralis besi agar dapat melihat kegiatan di dalam kolam renang. Terlebih dengan alasan tak mau mengganggu kami berdua, saya dan Maya. Saya pun menceritakan kejadian aneh di dalam kamar mandi tadi pada Maya. Setelah cerita saya usai. Seseorang mendeham dari belakang. Dan orang itu adalah Bayu yang telah selesai makan. Dan saya pun tak menaruh curiga apapun terhadapnya waktu itu. Hendra mulai menangis. Ibunya menidurkan kepala Hendra ke atas pundaknya. Tadinya saya ingin mengantar pulang Maya ke rumah. Namun dari tadi pikiran saya cemas terhadap sosok Bayu. Saya pun meminta izin Maya, dan pulang menelusuri jalan di sepanjang kali yang biasa saya dan Karmin lewati sesudah pulang dari kolam renang. Jika sore jalan itu memang selalu sepi. Oleh karenanya kami senang jika berjalan di sana. Dan tak jauh dari jalan masuk ke kali saya melihat Karmin dalam keadaan terbaring dan banyak luka. Saya pun berlari meminta bantuan Pak Joko. Kemudian saya berlari menemui Tante. Hendra mendongak melihat Mimin yang sudah berlinang air mata. Dokter Fadli mendatangi kerumunan kecil itu. Dan memegang dengan lembut pundak Mimin. Mimin melirik ke arah asal pegangan itu. Diraihnya tangan pada pundaknya sama lembut. Seakan beban yang begitu berat beralih tangan dan hilang seketika. Min, bagaimana soal operasinya? Dokter Fadli menatap dengan hangat wajah Mimin. Mimin menggenggam erat tangan lelaki yang pernah menjadi pacarnya itu sejenak lalu menciumnya. Aku percayakan padamu. **** Emosi saya meluap tak tahu arah. Ibu yang melihat air mata saya jatuh, langsung mendekap saya dan ikut menangis. Seperti tahu rasa sakit hati dan pendustaan ini, Ibu berkata Sabar ya, Kaka! sambil mengeluselus punggung. Namun saya membuang pelukan Ibu. Di hadapan Ibu, saya menengadahkan kedua tangan dan memelas, Mana kelamin saya, Bu? Ibu kembali mendekap saya. Dan saya lebih berontak meminta hak saya. Ibu tak berhak atas kelamin saya. Mana kelamin saya, Bu? Seperti naga yang mengenduskan bara api. Saya pun mendorong Ibu. Ibu tersungkur di tembok. Sejurus Ibu berdiri tegak lalu membuka pintu kamar. Dua orang pria tegap masuk memaksa. Salah satunya pria yang menyambut tadi sore. Pria tadi sore membawa kotak yang langsung diserahkan pada Ibu. Dan yang satunya menekel saya. Dari belakang kedua tangannya kokoh memegang kedua lengan saya. Saya berontak namun percuma. Ibu pun membuka kotak tadi. Asap dingin keluar ketika kotak dibuka. Ibu menyerahkan kehadapanku lalu memberi isyarat pada pria di belakangku. Perlahan tangannya kendor. Saya pun segera melepaskan tangannya, meraih kotak yang disodorkan Ibu. Saya bersandar pada badan tempat tidur, meratapi kelamin yang sudah beku dan bonyok kena tendangan. Akhirnya saya pun teringat sesuatu. Saya terkena tendangan keras yang di arahkan pada kelamin ini. Ibu melihat perubahan drastis pada wajah saya, dia pun berlutut, mengelus-elus rambut, Ada apa, Kak? tanyanya.
Tidak ada, sambil menggelengkan kepala. Ibu lantas berdiri. Bu..., Ibu langsung melihatku tajam. Kata Hendra siapa yang berbuat ini padaku Bu? Tanyaku sekenanya. Bayu. Saya tidak tahu Bayu itu siapa? Jangan paksakan diri, Pinta Ibu lembut. Benar, Bu. Sungguh! Yakin sekali. Seingatku, selesai makan. Kami berdua pulang bersama menelusuri jalan di pinggir kali. Seperti biasa. Ibu berang. Dan pergi begitu saja bersama kedua pria berseragam tadi. Dan saya tersenyum buaya puas akan apa yang akan menimpa Hendra.
Anda mungkin juga menyukai
- Biodata Operator Emis DtaDokumen1 halamanBiodata Operator Emis DtaHadi SubariBelum ada peringkat
- Presensi Berita Acara USP 2022Dokumen45 halamanPresensi Berita Acara USP 2022Hadi SubariBelum ada peringkat
- Enam Cara Jitu Menulis CeritaDokumen13 halamanEnam Cara Jitu Menulis CeritaHadi SubariBelum ada peringkat
- Projek TIK StorylineDokumen3 halamanProjek TIK StorylineHadi SubariBelum ada peringkat
- LKSD Project 1 Kelas X - Intergrasi KomputerDokumen5 halamanLKSD Project 1 Kelas X - Intergrasi KomputerHadi SubariBelum ada peringkat
- Cara Upload Revisi Portofolio Via Link Google DriveDokumen2 halamanCara Upload Revisi Portofolio Via Link Google DriveHadi SubariBelum ada peringkat
- Supervisi Adm KelasDokumen1 halamanSupervisi Adm KelasHadi SubariBelum ada peringkat
- Jalan Cinta para PejuangDokumen6 halamanJalan Cinta para PejuangBillal Maydika Aslam100% (3)
- Pengkajian Pustaka Dalam Penyusunan Proposal Penelitian1Dokumen24 halamanPengkajian Pustaka Dalam Penyusunan Proposal Penelitian1Hadi SubariBelum ada peringkat
- Pengajuan Barang TunaiDokumen4 halamanPengajuan Barang TunaiHadi SubariBelum ada peringkat
- Tugas MengindraDokumen4 halamanTugas MengindraHadi SubariBelum ada peringkat
- Alamat TujuanDokumen1 halamanAlamat TujuanHadi SubariBelum ada peringkat
- Tugas Acuan KhususDokumen3 halamanTugas Acuan KhususHadi SubariBelum ada peringkat
- Minggu Ke-1 Feb (Masih Rencana)Dokumen1 halamanMinggu Ke-1 Feb (Masih Rencana)Hadi SubariBelum ada peringkat
- Daftar Harga Ergin Feb 2012Dokumen2 halamanDaftar Harga Ergin Feb 2012Hadi SubariBelum ada peringkat
- Contoh LamaranDokumen1 halamanContoh LamaranHadi SubariBelum ada peringkat
- Dramatis As IDokumen3 halamanDramatis As IHadi SubariBelum ada peringkat
- Citation Dan ReferensiDokumen10 halamanCitation Dan ReferensiHadi SubariBelum ada peringkat
- AfiksasiDokumen10 halamanAfiksasiBoxir KecutBelum ada peringkat
- Daftar Riwayat HidupDokumen2 halamanDaftar Riwayat HidupHadi SubariBelum ada peringkat
- Kriptografi 01Dokumen61 halamanKriptografi 01Hadi SubariBelum ada peringkat
- Laporan SiswaDokumen3 halamanLaporan SiswaHadi SubariBelum ada peringkat
- Penulisan AbstrakDokumen2 halamanPenulisan AbstrakHadi SubariBelum ada peringkat
- Pengajuan 29 Maret 2012Dokumen1 halamanPengajuan 29 Maret 2012Hadi SubariBelum ada peringkat
- PasswordDokumen2 halamanPasswordHadi SubariBelum ada peringkat
- BON Dari ITCDokumen1 halamanBON Dari ITCHadi SubariBelum ada peringkat
- Bakat Dan KemauanDokumen1 halamanBakat Dan KemauanHadi SubariBelum ada peringkat