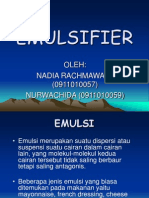HIPERTENSI
HIPERTENSI
Diunggah oleh
Andhika Ferdinando SitumorangHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
HIPERTENSI
HIPERTENSI
Diunggah oleh
Andhika Ferdinando SitumorangHak Cipta:
Format Tersedia
BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
2.1 Hipertensi
2.1.1 Definisi Hipertensi
Berdasarkan Joint National Commitee on Prevention Detection,
Evaluation, and Treatment of High Pressure (JNC 7), hipertensi adalah
peningkatan tekanan darah diatas normal, yaitu tekanan darah sistolik
140 mmHg dan atau Tekanan darah diastolik 90mmHg (Chobanian, et
al. 2003).
Definisi lain menyatakan hipertensi merupakan tekanan darah
sistolik lebih atau sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastolik
lebih atau sama dengan 90 mmHg atau mengkonsumsi obat
antihipertensi atau telah dinyatakan mengalami tekanan darah tinggi
oleh tenaga kesehatan setelah melakukan pemeriksaan minimal
sebanyak dua kali (AHA, 2013; Sinaga, 2010).
2.1.2
Klasifikasi Hipertensi
Menurut The Seventh Report of The Joint National Committe on
Prevention, Detection, Evaluaion, and Treatment of High Blood
Pressure (JNC 7) klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa terbagi
menjadi kelompok normal, prahipertensi, hipertensi derajat 1 dan
derajat 2 yang ditunjukkan pada tabel 2.1 (Chobanian, et al. 2003).
Tabel 2.1 Klasifikasi hipertensi menurut JNC VII
Klasifikasi
Tekanan sistolik
Dan/atau
Tekanan
tekanan darah
(mmHg)
Normal
Pre hipertensi
Hipertensi derajat 1
Hipertensi derajat 2
120
120-139
140-159
160
Dan
Atau
Atau
Atau
diastolik
(mmHg)
80
80-89
90-99
100
Berdasarkan etiologinya hipertensi dibagi menjadi dua
golongan, yaitu: hipertensi esensial atau hipertensi primer dan
hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan peningkatan tekanan
darah secara persisten yang belum diketahui secara pasti penyebabnya,
lebih dari 90% dari hipertensi tidak diketahui penyebabnya dan
tergolong pada hipertensi primer. Umumnya, hipertensi primer tidak
disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan disebabkan oleh beberapa
faktor yang berkaitan seperti genetik, peningkatan aktivitas dari sistem
saraf simpatis, sistem renin-angiotensin, ketidakmampuan ginjal untuk
mengekskresikan natrium pada tekanan darah normal, peningkatan
tahanan perifer dari arteriola, faktor hormonal, lingkungan, dan faktorfaktor yang meningkatkan resiko seperti, merokok, alkohol, dan
obesitas (Geyer dan Gomez, 2009; Zandi, 2013).
Kurang dari 10% penderita hipertensi sekunder dari penyakit
komorbid atau obat-obatan tertentu yang dapat meningkatkan tekanan
darah. Penyebab hipertensi sekunder yang telah diketahui antara lain
penyakit ginjal, hipertensi vaskular ginjal, hipertirodisme,
hiperaldosteronisme primer, sindrom cushing, koarktasio aorta,
feokromasitoma, obat-obatan, dan hipertensi yang berhubungan dengan
kehamilan (Geyer dan Gomez, 2009; Kaplan dan Weber, 2010).
2.1.3
Faktor Resiko
Hipertensi merupakan penyakit yang timbul karena interaksi
berbagai faktor resiko. Beberapa diantaranya ada yang tidak dapat
dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak dapat
dimodifikasi adalah kerturunan (genetik), jenis kelamin, dan umur
(Julius, 2008).
Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan
menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Hal
ini berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan
rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium. Individu yang
memiliki orang tua dengan hipertensi mempunyai risiko dua kali lebih
besar untuk menderita hipertensi dari pada orang yang tidak
mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Selain itu didapatkan
70-80% kasus hipertensi esensial dengan riwayat hipertensi dalam
keluarga (Anggraini, et al. 2009).
Jenis kelamin mempunyai pengaruh penting dalam regulasi
tekanan darah. Prevalensi terjadinya hipertensi antara pria dan wanita
hampir sama. Akan tetapi, wanita terlindungi oleh hormon estrogen dari
penyakit kardiovaskular sebelum menopause. Hormon estrogen
berperan dalam meningkatkan kadar High Density Lipoprotein (HDL).
Kadar HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam mencegah
arterosklerosis. Prevalensi hipertensi pada wanita meningkat pada saat
wanita mulai kehilangan hormon estrogen pada masa premenopause
saat usia 45-55 tahun (Kumar, 2008).
Beberapa penelitian yang dilakukan, ternyata terbukti bahwa
semakin tinggi umur seseorang maka semakin tinggi tekanan darahnya.
Hal ini disebabkan elastisitas dinding pembuluh darah semakin
menurun dengan bertambahnya umur. Sebagian besar hipertensi terjadi
pada umur lebih dari 65 tahun. Sebelum umur 55 tahun tekanan darah
pada laki laki lebih tinggi daripada perempuan. Setelah umur 65
tekanan darah pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Dengan
demikian, risiko hipertensi bertambah dengan semakin bertambahnya
umur (Gray, et al. 2005).
Adapun faktor resiko yang dapat dimodifikasi adalah merokok,
aktivitas fisik, asupan natrium dan garam. Merokok dapat
meningkatkan beban kerja jantung dan menaikkan tekanan darah.
Menurut penelitian, diungkapkan bahwa merokok dapat meningkatkan
tekanan darah. Nikotin yang terdapat dalam rokok sangat
membahayakan kesehatan, karena nikotin dapat meningkatkan
penggumpalan darah dalam pembuluh darah dan dapat menyebabkan
pengapuran pada dinding pembuluh darah. Nikotin bersifat toksik
terhadap jaringan saraf yang menyebabkan peningkatan tekanan darah
baik sistolik maupun diastolik, denyut jantung bertambah, kontraksi
otot jantung meningkat, pemakaian oksigen bertambah, aliran darah
pada koroner meningkat dan vasokontriksi pada pembuluh darah perifer
(Gray, et al. 2005).
Asupan natrium dan garam tergolong faktor resiko hipertensi
yang kontroversial. Beberapa individu peka terhadap natrium, baik
yang berasal dari garam kemasan atau bahan lain yang mengandung
natrium, dan hidangan cepat saji, tetapi respon terhadap natrium pada
setiap orang tidak sama. Natrium merupakan salah satu bentuk mineral
atau elektrolit yang berpengaruh terhadap tekanan darah. Peningkatan
asupan mineral lain mungkin sama pentingnya atau lebih penting
daripada penurunan asupan natrium bagi seseorang (Stephen, et.al
2010).
Asupan garam yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran
berlebihan hormon natriuretik yang secara tidak langsung akan
meningkatkan tekanan darah. Kebiasaan merokok berpengaruh dalam
meningkatkan risiko hipertensi walaupun mekanisme timbulnya
hipertensi belum diketahui secara pasti (Anggraini, 2009).
2.1.4
Patofisiologi Hipertensi
Peningkatan tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan
resistensi perifer yang memiliki interaksi kompleks dengan berbagai
faktor seperti genetik, lingkungan, dan demografi. Total curah jantung
dipengaruhi oleh volume darah, sementara volume darah sangat
bergantung pada homeostasis natrium. Hormonal dan persarafan
mempengaruhi resistensi perifer total pada tingkat arteriol. Tonus
vaskular normal mencernimkan keseimbangan antara vasokonstriktor
humoral (katekolamin dan angiotensin II) dan vassodilator seperti nitrat
oksida, prostaglandin, dan kinin (Kumar, 2008).
10
Sistem renin angiotensin aldosteron (RAA) memainkan peranan
penting proses terjadinya hipertensi. Renin adalah enzim dengan protein
kecil yang disimpan dan disintesis dalam bentuk inaktif yang disebut
prorenin dalam sel-sel jukstaglomelular pada ginjal dan akan dilepaskan
dalam darah bila ginjal mendeteksi tekanan yang rendah pada arteri.
Renin bekerja secara enzimatik pada protein plasma lain yaitu suatu
globulin yang disebut bahan renin atau angiotensinogen, untuk
melepaskan peptida asam amino-10 yaitu angiotensin I. Pada fungsi
sirkulasi, angiotensin I memiliki sifat sebagai vasokonstriktor ringan
tetapi tidak cukup untuk menyebabkan perubahan fungsional yang
bermakna. Renin menetap dalam darah selama kurang lebih satu jam
dan menyebabkan pembentukan angiotensin I pada selang waktu
tersebut (Guyton, 2007).
Beberapa detik setelah pembentukan angiotensin I, terdapat dua
asam amino tambahan yang memecah dari angiotensin untuk
membentuk angiotensin II peptide asam amino-8. Perubahan ini hampir
terjadi seluruhnya selama beberapa detik. Peptida ini selanjutnya
dibawa oleh darah melalui pembuluh kecil pada paru-paru dan akan
diubah menjadi Angiotensin II oleh suatu enzim pengubah yang
terdapat pada endotel pembuluh darah paru. Enzim ini adalah
Angiotensin Converting Enzyme (ACE). Angiotensin II merupakan
vasokonstriktor kuat dan memiliki efek lain yang juga mempengaruhi
sirkulasi. Tidak seperti angiotensin I, angiotensin II menetap dalam
darah hanya selama kurang lebih dua menit karena angiotensin II akan
11
diinaktifkan oleh berbagai enzim darah dan jaringan secara cepat.
Enzim tersebut bersama-sama disebut angiotensinase (Guyton, 2007).
Angiotensin II mempunyai dua pengaruh utama dalam
meningkatkan tekanan arteri selama berada di dalam darah. Pengaruh
pertama yaitu sebagai vasokonstriksi yang timbul secara cepat.
Vasokonstriksi terutama terjadi pada arteri dibandingkan pada vena.
Konstriksi pada arteriol akan meningkatkan tahanan perifer akibatnya
akan meningkatkan tekana arteri. Peningkatan aliran darah balik vena
ke jantung juga terjadi akibat kontriksi ringan pada pembuluh vena,
sehingga membantu pompa jantung melawan kenaikan tekanan
(Guyton, 2007).
Pengaruh angiotensin II yang kedua dalam hal peningkatan
tekanan darah adalah dengan bekerja pada ginjal untuk menurunkan
ekskresi garam dan air. Terdapat dua mekanisme kerja angiotensin II
pada ginjal, yang pertama yaitu peningkatan sekresi hormon
antidiuretik (ADH). Produksi ADH terjadi di hipotalamus (kelenjar
pituitari) dan mengatur osmalaritas dan volume urin ketika bekerja
dalam ginjal. Dengan meningkatnya ADH, urin yang diekskresikan ke
luar tubuh menjadi sedikit (antidiuresis), sehingga urin menjadi pekat
dan tinggi osmolaritasnya. Untuk mengencerkannya, cairan harus
ditarik dari intraselular ke ekstravaskular agar terjadi peningkatan
cairan ekstravaskular. Tekanan darah akan mengalami peningkatkan
karena volume darah yang meningkat. Mekanisme kedua adalah
menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron
12
merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal.
Aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl (garam) denagn
merabsorspsinya dari tubulus ginjal untuk mengatur volume
ekstraseluler. Peristiwa ini akan meningkatkan konsentrasi NaCl yang
kemudian akan diencerkan kembali dengan meningkatkan volume
cairan ekstraselular yang akhirnya akan meningkatkan volume dan
tekanan darah (Guyton, 2007).
Setiap kemungkinan penyebab hipertensi yang disebutkan diatas
dapat terjadi akibat peningkatan aktivitas susunan saraf simpatis atau
responsivitas berlebihan dari tubuh terhadap rangsagan simpatis normal
dapat menyebabkan hipertensi. hal ini terjadi pada stress jangka
panjang yang diketahui melibatkan pengaktifan sistem simpatis atau
akibat berlebihnya genetik reseptor norepinefrin di jantung atau otot
polos vaskular (Corwin, 2009).
2.1.5
Diagnosis Hipertensi
Dalam menegakkan diagnosis pasien hipertensi yang harus
dilakukan adalah anamnesis tentang keluhan pasien, riwayat penyakit
dahulu dan riwayat penyakit keluarga pasien, pemeriksaan fisik serta
pemeriksaan penunjang. Seseorang dikatakan hipertensi jika pada dua
kali atau lebih kunjungan yang berbeda didapatkan tekanan darah ratarata dari dua atau lebih pengukuran setiap kunjungan, tekanan darah
diastolik 90 mmHg atau lebih, dan atau tekanan darah diastolik 140
mmHg atau lebih. Selain itu, evaluasi terhadap penyakit penyerta,
kerusakan organ target serta kemungkinan adanya hipertensi essensial
13
juga harus dilakukan untuk mendukung diagnosis hipertensi
(Yogiantoro, 2009).
2.1.6
Penatalaksanaan Hipertensi
Tujuan umum pengobatan hipertensi adalah penurunan
mortalitas dan morbiditas yang berhubungan dengan hipertensi.
Mortalitas dan morbiditas ini berhubungan dengan kerusakan organ
target (misal: kejadian kardiovaskular atau serebrovaskular, gagal
jantung, dan penyakit ginjal). Mengurangi risiko merupakan tujuan
utama terapi hipertensi, dan pilihan terapi obat dipengaruhi secara
bermakna oleh bukti yang menunjukkan pengurangan resiko
(Chobanian, et al, 2003). Guideline tata laksana hipertensi di antaranya
adalah dari JNC 7 (2003) dan dari ESC/ESH (2007). Keduanya
merupakan rujukan utama tatalaksana hipertensi (Tedjasukmana, 2012).
2.1.6.1 Target tekanan darah
Pengobatan hipertensi dilakukan dengan tujuan untuk
mencapai tekanan darah target. Sekali obat antihipertensi
digunakan, selanjutnya sangat diperlukan pemeriksaan rutin
untuk menilai perkembangan pengobatan yang dilakukan.
Pemeriksaan rutin dilakukan paling tidak sebulan sekali, dan
kunjungan akan lebih sering pada pasien dengan hipertensi stage
2 atau pasien dengan penyakit penyerta. Jika pasien telah
mencapai tekanan darah target, follow up dapat dilakukan dalam
interval 3-6 bulan sekali. Namun, jika dalam 6 bulan target
tekanan darah tidak tercapai dengan penggunaan obat dosis
14
optimal dan kombinasi beberapa obat yang sesuai,
dipertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis
(Yogiantoro, 2009).
Menurut Joint National Committee (JNC) 7,
rekomendasi target tekanan darah yang harus dicapai adalah <
140/90 mmHg dan target tekanan darah untuk pasien penyakit
ginjal kronik dan diabetes adalah 130/80 mmHg. American
Heart Association (AHA) merekomendasikan target tekanan
darah yang harus dicapai, yaitu 140/90 mmHg, 130/80 mmHg
untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik, penyakit arteri
kronik atau ekuivalen penyakit arteri kronik, dan 120/80
mmHg untuk pasien dengan gagal jantung (Chobanian et al,
2003). Sedangkan menurut National Kidney Foundation (NKF),
target tekanan darah yang harus dicapai adalah 130/80 mmHg
untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik dan diabetes, dan <
125/75 mmHg untuk pasien dengan > 1 g proteinuria (Cohen,
2008).
2.1.6.2 Terapi non farmakologi
Menjalani pola hidup sehat telah banyak terbukti dapat
menurunkan tekanan darah, dan secara umum sangat
menguntungkan dalam menurunkan risiko permasalahan
kardiovaskular. Pada pasien yang menderita hipertensi derajat 1,
tanpa faktor risiko kardiovaskular lain, maka strategi pola hidup
sehat merupakan tatalaksana tahap awal, yang harus dijalani
15
setidaknya selama 4 sampai 6 bulan. Bila setelah jangka waktu
tersebut, tidak didapatkan penurunan tekanan darah yang
diharapkan atau didapatkan faktor risiko kardiovaskular yang
lain, maka sangat dianjurkan untuk memulai terapi farmakologi
(Soenarta, et al. 2015).
Beberapa pola hidup sehat yang dianjurkan oleh banyak
guidelines yaitu pertama, penurunan berat badan dapat
dilakukan dengan cara mengganti makanan tidak sehat dengan
memperbanyak asupan sayuran dan buah-buahan dapat
memberikan manfaat yang lebih selain penurunan tekanan
darah, seperti menghindari diabetes dan dislipidemia (Soenarta,
et al. 2015).
Kedua, diet rendah garam. Di negara kita, makanan
tinggi garam dan lemak merupakan makanan tradisional pada
kebanyakan daerah. Tidak jarang pula pasien tidak menyadari
kandungan garam pada makanan cepat saji, makanan kaleng,
daging olahan dan sebagainya. Dianjurkan untuk asupan garam
tidak melebihi 2 gr/hari (Soenarta, et al. 2015).
Ketiga, olahraga yang dilakukan secara teratur sebanyak
30 60 menit/hari, minimal 3 hari/minggu, dapat menolong
penurunan tekanan darah. Terhadap pasien yang tidak memiliki
waktu untuk berolahraga secara khusus, sebaiknya harus tetap
dianjurkan untuk berjalan kaki, mengendarai sepeda atau
16
menaiki tangga dalam aktifitas rutin mereka di tempat kerjanya
(Soenarta, et al. 2015).
Keempat, mengurangi konsumsi alkohol. Walaupun
konsumsi alkohol belum menjadi pola hidup yang umum di
negara kita, namun konsumsi alkohol semakin hari semakin
meningkat seiring dengan perkembangan pergaulan dan gaya
hidup, terutama di kota besar. Konsumsi alkohol lebih dari 2
gelas per hari pada pria atau 1 gelas per hari pada wanita, dapat
meningkatkan tekanan darah. Dengan demikian membatasi atau
menghentikan konsumsi alkohol sangat membantu dalam
penurunan tekanan darah (Soenarta, et al. 2015).
Kelima, berhenti merokok. Walaupun hal ini sampai saat
ini belum terbukti berefek langsung dapat menurunkan tekanan
darah, tetapi merokok merupakan salah satu faktor risiko utama
penyakit kardiovaskular, dan pasien sebaiknya dianjurkan untuk
berhenti merokok (Soenarta, et al. 2015).
2.1.6.3 Terapi farmakologis.
Obat antihipertensi perlu dimulai berdasarkan pada 2
kriteria: 1) tingkatan tekanan darah sistolik dan diastolik, dan 2)
tingkatan risiko kardiovaskular (tabel 2.2).
Jenis-jenis obat antihipertensi untuk terapi farmakologis
yang dianjurkan oleh JNC 7 adalah diuretika, terutama jenis
Thiazide (Thiaz) atau Aldosterone antagonist (Aldo Ant), Beta
17
Blocker (BB), Calcium Channel Blocker atau Calcium
antagonist (CCB), Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
(ACEI), Angiotensin II Receptor Blocker atau AT1 receptor
antagonist/blocker (Chobanian, et al. 2003 ; Yogiantoro, 2006).
Diuretika golongan tiazid bekerja meningkatkan ekskresi
natrium, air dan klorida sehingga menurunkan volume darah dan
cairan ekstraseluler akibatnya terjadi penurunan curah jantung
dan tekanan darah. Adapun yang termasuk golongan tiazid yaitu
hidroklorotiazid (HCT), klortalidon, indapamid,
bendroflumetiazid, metolazon dan xipamid (Chobanian, et al.
2003; Yogiantoro, 2006).
Obat golongan beta bloker terbagi menjadi kardioselektif
dan non selektif. Golongan kardioselektif terdiri dari asebutolol,
atenolol, bisoprolol, dan metoprolol. Sedangkan golongan non
selektif terdiri dari alprenolol, karteolol, nadolol, oksprenolol,
pindolol, propranolol, timolol, karvedilol, dan labetalol
(Chobanian, et al. 2003; Yogiantoro, 2006).
Beberapa obat yang termasuk dalam golongan antagonis
kalsium yaitu nifedipin, verapamil, diltiazem, amlodipin,
nikardipin, isradipin, felodipin (Chobanian, et al. 2003;
Yogiantoro, 2006).
Golongan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
(ACEI) terdiri atas captopril, benazepril, enalapril, fosinopril,
lisinopril, perindopril, quinapril, trandolapril, dan imidapril.
18
Beberapa obat yang tergolong ARB yaitu losartan, valsartan,
irbesartan, telmisartan, dan candesartan (Chobanian, et al. 2003;
Yogiantoro, 2006).
Tabel 2.2 Penanganan tekanan darah tinggi berdasarkan
klasifikasi (Chobanian, et al. 2003).
Klasifikasi
tekanan
darah
Modifikasi
gaya hidup
Normal
Prehipertensi
Anjuran
Ya
Hipertensi
stage 1
Ya
Hipertensi
stage 2
Ya
Obat Awal
Tanpa indikasi
Dengan indikasi
Tidak Perlu
menggunakan
obat
antihipertensi
Untuk semua
kasus gunakan
diuretik jenis
thiazide,
pertimbangkan
ACEi, ARB,
BB, CCB, atau
kombinasikan
Gunakan
kombinasi 2
obat (biasanya
diuretik jenis
thiazide dan
ACEi/ARB/BB/
CCB
Gunakan obat
yang spesifik
dengan indikasi
(resiko).
Gunakan obat
yang spesifik
dengan indikasi
(resiko).
Kemudian
tambahkan obat
antihipertensi
(diretik, ACEi,
ARB, BB, CCB)
seperti yang
dibutuhkan
2.2 Kepatuhan
2.2.1 Definisi Kepatuhan
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, patuh adalah suka
menurut perintah, taat pada perintah. Sedangkan kepatuhan adalah
perilaku sesuai aturan dan berdisplin (Departemen Pendidikan
Nasional, 2008). Kepatuhan terhadap pengobatan diartikan secara
umum sebagai tindakan perilaku dimana pasien menggunakan obat dan
19
mentaati semua aturan dan nasihat yang dianjurkan oleh tenaga
kesehatan (Osterberg dan Blashke, 2005).
Kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku
yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan
(Notoatmodjo, 2007).
Kepatuhan minum obat adalah keselarasan pasien dengan
rekomendasi pelayan kesehatan yang sesuai dengan waktu, dosis, dan
frekuensi menggunakan obat sepanjang waktu yang ditentukan
(Chowdhury, 2013).
2.2.2
Cara mengukur kepatuhan
Terdapat dua metode yang bisa digunakan untuk mengukur
kepatuhan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.
Pengukuran kepatuhan dengan metode langsung dapat dilakukan
dengan observasi pengobatan secara langsung, mengukur konsentrasi
obat dan metabolitnya dalam darah atau urin serta mengukur biologic
marker yang ditambahkan pada formulasi obat. Kelemahan metode ini
adalah biayanya yang mahal, memberatkan tenaga kesehatan dan rentan
terhadap penolakan pasien (Osterberg dan Blaschke, 2005).
Metode tidak langsung dapat dilakukan dengan menanyakan
pasien tentang cara pasien menggunakan obat, menilai respon klinik,
melakukan perhitungan obat (pill count), menilai angka refilling
prescriptions, mengumpulkan kuesioner pasien, menggunakan
electronic medication monitor, menilai kepatuhan pasien anak dengan
menanyakan kepada orang tua (Osterberg dan Blaschke, 2005).
20
Pengukuran tingkat kepatuhan dapat menggunakan kuesioner.
Metode ini cukup sederhana, murah dan mudah dilakukan. Kuesioner
Morisky scale sudah terbukti dan tervalidasi bisa digunakan untuk
mengukur kepatuhan penggunaan obat pada penyakit-penyakit terapi
jangka panjang seperti diabetes mellitus, jantung koroner dan hipertensi
(Morisky, et al, 2008).
2.2.3
Kuesioner Morisky Scale 8-items
Salah satu metode pengukuran kepatuhan secara tidak langsung
adalah dengan menggunakan kuesioner. Metode ini dinilai cukup
sederhana, murah dalam pelaksanaannya. Salah satu model kuesioner
yang telah tervalidasi untuk menilai kepatuhan terapi jangka panjang
adalah Morisky scale 8-items. Pada mulanya Morisky mengembangkan
beberapa pertanyaan singkat (dengan 4 butir pertanyaan) untuk
pengukur kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. Namun saat ini
kuesioner Morisky Scale telah dimodifikasi menjadi 8 pertanyaan
dengan modifikasi beberapa pertanyaan sehinggan lebih lengkap dalam
penelitian kepatuhan. Modifikasi kuesioner Morisky tersebut saat ini
telah dapat digunakan untuk pengukuran kepatuhan pengobatan
penyakit yang memerlukan terapi jangka panjang (Morisky, et al, 2008).
2.3 Kerangka Teori
Menurunkan BB
Diet rendah garam
Olahraga teratur
Pola Hidup
Sehat
Pencapaian Target
Tekanan Darah
Kurangi konsumsi
alkohol
21
Berhenti merokok
Kepatuhan
minum obat
Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian
2.4 Kerangka Konsep
Kepatuhan minum obat
Pencapaian Target
Tekanan Darah
Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian
2.5 Hipotesis penelitian
Ada hubungan antara tingkat kepatuhan minum obat terhadap pencapaian
target tekanan darah pada penderita hipertensi di poliklinik lanjut usia (lansia)
Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Pekanbaru.
Anda mungkin juga menyukai
- Patofisiologi FimosisDokumen1 halamanPatofisiologi FimosisAndhika Ferdinando Situmorang0% (1)
- Laporan Kasus Limfadenitis TBDokumen24 halamanLaporan Kasus Limfadenitis TBAndhika Ferdinando Situmorang100% (1)
- Otitis EksternaDokumen11 halamanOtitis EksternaAndhika Ferdinando SitumorangBelum ada peringkat
- Referat Hernia InguinalisDokumen27 halamanReferat Hernia InguinalisAndhika Ferdinando Situmorang100% (3)
- Asi EksklusifDokumen30 halamanAsi EksklusifAndhika Ferdinando Situmorang100% (1)
- EmulsifierDokumen31 halamanEmulsifierAndhika Ferdinando SitumorangBelum ada peringkat
- RADIOLOGIDokumen89 halamanRADIOLOGIAndhika Ferdinando SitumorangBelum ada peringkat
- ShampooDokumen12 halamanShampooDjlab AlcatrazBelum ada peringkat