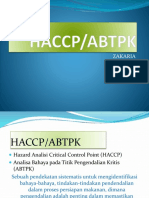Surveilanse Gizi
Surveilanse Gizi
Diunggah oleh
Vina Soumokil0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
20 tayangan5 halamangizi
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen Inigizi
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
20 tayangan5 halamanSurveilanse Gizi
Surveilanse Gizi
Diunggah oleh
Vina Soumokilgizi
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 5
Surveilans Epidemiologi Gizi Buruk
Pengertian dan Dasar Pelaksanaan Surveilans Gizi Buruk
Berbagai penelitian menunjukkan dampak serius masalah gizi buruk terhadap
kesehatan, bahkan terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Dampak jangka pendek
gizi buruk terhadap perkembangan anak antara lain anak menjadi apatis, mengalami
gangguan bicara serta gangguan perkembangan lain. Sementara dampak jangka panjang
berupa penurunan skor intelligence quotient (IQ), penurunan perkembangan kognitif,
penurunan integrasi sensori, gangguan pemusatan perhatian, gangguan penurunan rasa
percaya diri serta akan menyebabkan merosotnya prestasi di sekolah.
Kurang gizi juga berpotensi menjadi penyebab kemiskinan melalui rendahnya
kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Gizi buruk yang tidak dikelola dengan
baik, pada fase akutnya akan mengancam jiwa dan pada jangka panjang akan menjadi
ancaman hilangnya sebuah generasi penerus bangsa.
Mengingat dampak yang sedemikain serius tersebut, sudah seyogyanya seluruh
potensi dan komponen dikerahkan untuk mencegah dan menangulangi masalah gizi
buruk ini. Tindakan penting terkait usaha pencegahan antara lain dengan melakukan
kegiatan surveilans epidemiologi masalah gizi ini.
Banyak pengertian surveilans yang sudah umum dikenal selama ini. Antara lain
menurut WHO, surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan
interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada
unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Berdasarkan definisi diatas
dapat diketahui bahwa surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang
dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit
serta faktor-faktor yang mempengaruhi nya pada masyarakat sehingga dapat dilakukan
penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan efektif.
Menurut Timmreck (2005), surveilans kesehatan masyaraka adalah proses
pengumpulan data kesehatan yang mencakup tidak saja pengumpulan informasi secara
sistematik, tetapi juga melibatkan analisis, interpretasi, penyebaran, dan penggunaan
informasi kesehatan. Hasil surveilans dan pengumpulan serta analisis data digunakan
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang status kesehatan populasi guna
merencanakan, menerapkan, mendeskripsikan, dan mengevaluasi program kesehatan
masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah kejadian yang merugikan kesehatan.
Dengan demikian, agar data dapat berguna, data harus akurat, tepat waktu, dan tersedia
dalam bentuk yang dapat digunakan.
Terdapat beberapa aktivitas inti surveilans kesehatan masyarakat tersebut.
Kegiatan surveilans kesehatan masyarakat antara lain :
1. Pendeteksian kasus (case detection): proses mengidentifikasi peristiwa atau
keadaan kesehatan. Unit sumber data menyediakan data yang diperl ukan dalam
penyelenggaraan surveilans epidemiologi seperti rumah sakit, puskesmas,
laboratorium, unit penelitian, unit program-sektor dan unit statistik.
2. Pencatatan kasus (registration): proses pencatatan kasus hasil identifikasi
peristiwa atau keadaan kesehatan.
3. Konfirmasi (confirmation): evaluasi dari ukuran-ukuran
4. epidemiologi sampai pada hasil percobaan laboratorium.
5. Pelaporan (reporting): data, informasi dan rekomendasi sebagai hasil kegiatan
surveilans epidemiologi disampaikan kepada pihak-pihak yang dapat melakukan
tindakan penanggulangan penyakit atau upaya peningkatan program kesehatan,
pusat penelitian dan pusat kajian serta pertukaran data dalam jejaring surveilans
epidemiologi. Pengumpulan data kasus pasien dari tingkat yang lebih rendah
dilaporkan kepada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi seperti lingkup daerah atau
nasional.
6. Analisis data (data analysis): analisis terhadap data-data dan angka-angka dan
menentukan i ndikator terhadap ti ndakan.
7. Respon segera dan kesiapsiagaan wabah (epidemic preparedness) kesiapsiagaan
dalam menghadapi wabah/kejadian luar biasa.
8. Respon terencana (response and control): sistem pengawasan kesehatan
masyarakat hanya dapat digunakan jika data yang ada bisa digunakan dalam
peringatan dini dan munculnya masalah dalam kesehatan masyarakat.
9. Umpan balik (feedback) yang berfungsi penting dari semua sistem pengawasan,
alur pesan dan informasi kembali ke tingkat yang lebih rendah dari tingkat yang
lebih tinggi.
Secara umum tujuan surveilans adalah untuk pencegahan dan pengendalian
penyakit dalam masyarakat, sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan
terjadinya kejadian luar biasa (KLB), memperoleh informasi yang diperlukan bagi
perencanaan dalam hal pencegahan, penanggulangan maupun pemberantasannya pada
berbagai tingkat administrasi
Sedangkan komponen-komponen kegiatan surveilans antara lain:
1. Pengumpulan data, data yang dikumpulkan adalah data epidemiologi yang
jelas, tepat dan ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Tujuan
dari pengumpulan data epidemiologi adalah: untuk menentukan kelompok
populasi yang mempunyai resiko terbesar terhadap serangan penyakit; untuk
menentukan reservoir dari infeksi; untuk menentukan jenis dari penyebab
penyakit dan karakteristiknya; untuk memastikan keadaan yang dapat
menyebabkan berlangsungnya transmisi penyakit; untuk mencatat penyakit
secara keseluruhan; untuk memastikan sifat dasar suatu wabah, sumbernya,
cara penularannya dan seberapa jauh penyebarannya.
2. Kompilasi, analisis dan interpretasi data. Data yang terkumpul selanjutnya
dikompilasi, dianalisis berdasarkan orang, tempat dan waktu. Analisa dapat
berupa teks tabel, grafik dan spot map sehingga mudah dibaca dan merupakan
informasi yang akurat. Dari hasil analisis dan interpretasi selanjutnya dibuat
saran bagaimana menentukan tindakan dalam menghadapi masalah yang baru.
3. Penyebaran hasil analisis dan hasil interpretasi data. Hasil analisis dan
interpretasi data digunakan untuk unit-unit kesehatan setempat guna
menentukan tindak lanjut dan disebarluaskan ke unit terkait antara lain berupa
laporan kepada atasan atau kepada lintas sektor yang terkait sebagai informasi
lebih lanjut.
Sementara terkait dengan masalah gizi masyarakat, di Indonesia, beberapa dasar
hukum dan pedoman pelaksanaan surveilans gizi buruk antara lain :
1. Surat Menteri Kesehatan Nomor: 1209, tanggal 19 Oktober 1998 yang
menginstruksikan agar memperlakukan kasus gizi buruk sebagai sebuah
Kejadian Luar Biasa (KLB).
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1116/MENKES/SK/VI II/2003
tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Kesehatan
Pada Kepmenkes diatas, salah satu sasaran surveilans epidemilogi kesehatan
adalah pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Gizi (SKG) dan sistem kewaspadaan dini
kejadian luar biasa (SKD KLB) gizi buruk. Sedangkan berdasarkan Surveilans gizi
adalah pengamatan yang dilakukan terhadap anak balita dalam rangka mencegah
terjadinya kasus gizi buruk.
Sedangkan menurut WHO, praktek survailans gizi dilakukan dengan melakukan
pengamatan keadaan gizi, dalam rangka untuk membuat keputusan yang berdampak
pada perbaikan gizi penduduk dengan menyediakan informasi yang terus menerus
tentang keadaan gizi penduduk, berdasarkan pengumpulan data langsung sesuai sumber
yang ada, termasuk data hasil survei dan data yang sudah ada.
Terdapat tiga jenis utama sistem surveilans gizi menurut Mason et al (1984),
yaitu:
1. Pemantauan gizi jangka panjang sebagai masukan untuk perencanaan nasional,
untuk menganalisis dampak kebijakan dan untuk memprediksi kecenderungan
masa depan
2. Evaluasi dampak program gizi dan proyek-proyek tertentu yaitu informasi
yang dirancang untuk memungkinkan tanggapan langsung melalui program
atau proyek modifikasi
3. Peringatan dini atau sistem peringatan tepat waktu untuk mengidentifikasi
kekurangan pangan akut, untuk mendapatkan tanggapan jangka pendek.
Sistem Surveilans gizi adalah mengumpulkan data dasar program yang
difokuskan pada masalah gizi bayi, anak-anak, dan wanita hamil. Sistem surveilans gizi
berfungsi untuk menyediakan data lokal spesifik yang berguna untuk pengelolaan
program gizi kesehatan masyarakat. Sistem ini memberikan informasi yang sangat
berguna, tetapi juga ada tantangan metodologis yang berkaitan dengan keterwakilan,
pengawasan mutu, dan indikator sensitivitas atau spesifisitas.
Sementara menurut WHO menggambarkan sistem surveilans gizi sebagai proses
yang berkesinambungan memiliki lima tujuan khusus, antara lain :
1. Menggambarkan status gizi penduduk, dengan referensi khusus bagi mereka
yang menghadapi risiko
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab yang terkait dengan gizi buruk
3. Mempromosikan keputusan oleh pemerintah, baik mengenai perkembangan
normal dan keadaan darurat
4. Memprediksi kemungkinan masalah gizi sehingga dapat membantu dalam
perumusan kebijakan
5. Memantau dan mengevaluasi program gizi.
Ruang lingkup dan tujuan sistem surveilans gizi di Indonesia menurut Soekirman
& Karyadi (1995), antara sebagai berikut:
1. Sistem yang berfungsi sebagai peringatan dan intervensi tepat waktu.
2. Sistem untuk menghubungkan masalah daerah rawan (kabupaten, kecamatan,
desa) dengan otoritas yang lebih tinggi pada tingkat propinsi dan tingkat pusat.
3. Memberikan indikator yang berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini untuk
krisis pangan
4. Membimbing tindakan cepat untuk mengatasi penurunan ketersediaan pangan
dan konsumsi, khususnya di kalangan rumah tangga miskin
Referensi, antara lain :
Soekirman & Karyadi, D. (1995). Nutrition surveillance: A planners perspective.
Food and Nutrition Bulletin. United Nations University. Tokyo
Mason, et al. (1984). Nutritional Surveillance. WHO
Timmreck, C.T. (2005). Epidemiologi: Suatu Pengantar,. EGC.
Anda mungkin juga menyukai
- Konsep Dasar Ilmu GiziDokumen35 halamanKonsep Dasar Ilmu GiziVina Soumokil100% (1)
- Pengantar Dasar Ilmu GiziDokumen19 halamanPengantar Dasar Ilmu GiziVina SoumokilBelum ada peringkat
- Pangan Untuk Bayi Dan AnakDokumen29 halamanPangan Untuk Bayi Dan AnakVina SoumokilBelum ada peringkat
- Klasifikasi PanganDokumen3 halamanKlasifikasi PanganVina Soumokil100% (1)
- Biokimia BidanDokumen247 halamanBiokimia BidanVina SoumokilBelum ada peringkat
- 7 Prinsip HACCPDokumen26 halaman7 Prinsip HACCPVina SoumokilBelum ada peringkat