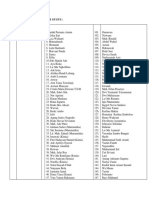176 Ismatul Hidayah PDF
176 Ismatul Hidayah PDF
Diunggah oleh
Deejay ShanellJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
176 Ismatul Hidayah PDF
176 Ismatul Hidayah PDF
Diunggah oleh
Deejay ShanellHak Cipta:
Format Tersedia
Kajian Dampak Penambangan Emas terhadap Aspek Sosial Ekonomi dan
Lingkungan Pertanian di Kabupaten Buru
Ismatul Hidayah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku
Jl. Chr Splanit Rumah Tiga Ambon
E-mail: ismatul_h@yahoo.co.id
Abstrak
Memperhatikan aktivitas masyarakat dalam penambangan emas serta kondisi ketersediaan pangan
terutama komoditas pertanian saat ini di wilayah kabupaten Buru, dapat memberikan suatu
gambaran pemikiran kelak pembangunan pertanian di wilayah tersebut menghadapi masalah besar
yang dapat menimbulkan kerawanan pangan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengidentifikasi dampak penambangan emas terhadap aspek social ekonomi dan lingkungan
pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran pertambangan emas di kabupaten Buru
pada umumnya memberikan dampak negatif pada aspek sosio-ekonomi dan ekologi yaitu
terjadinya penurunan pendapatan usahatani karena meningkatnya biaya produksi, kelangkaan
tenaga kerja dibidang pertanian karena sebagian besar beralih pada kegiatan tambang sehingga
memicu kenaikan upah tenaga kerja, keterbatasan dan meningkatnya harga-harga sembako,
tingginya komoditas beras dari luar yang masuk ke pulau buru sehingga mempengaruhi pemasaran
beras lokal. Pada aspek sosio - ekologi, yaitu terjadinya pencemaran lingkungan. Proses
pengolahan emas berada di halaman rumah dan kebun, memungkinkan terjadinya pencemaran
merkuri terhadap lingkungan hidup, terutama jika kolam penampungan tailing tidak ditangani
dengan baik. Selain itu proses penggarangan secara sederhana dilakukan di sekitar rumah, dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan oleh uap merkuri yang ditimbulkannya. Penanganan tailing
(limbah) dilakukan secara sederhana dengan kolam penampungan yang sangat terbatas, tanpa
disertai dengan pengelolaan yang baik, seperti misalnya tidak dilakukannya proses detoksifikasi,
degradasi, maupun penjernihan, sehingga material halus merkuri, arsen dan logam dasar masih
bercampur dalam tailing. Pengolahan emas dengan teknik amalgamasi telah menyebabkan
kontaminasi merkuri pada lingkungandi sekitarnya. Hasil analisis kimia terhadap sampel hasil
pertanian menunjukkan adanya kontaminasi merkuri dan logam berat diatas ambang batas.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang negatif dan berbahaya bagi
masyarakat di wilayah Kabupaten Buru. Pada aspek keamanan, sering terjadi bentrokan antara
warga asli dan warga pendatang yang menewaskan beberapa penambang dan tingginya tingkat
pencurian yang meresahkan masyarakat. Kondisi lingkungan yang tercemar akan menurunkan
tingkat kesehatan masyarakat secara perlahan2 dan dalam jangka panjang dikhawatirkan akan
terjadi tragedi seperti kasus teluk Buyat atau teluk minamata.
Kata kunci : dampak lingkungan, kabupaten Buru, penambangan emas, produksi pertanian.
Pendahuluan
Maluku meskipun tidak termasuk sentra produksi padi nasional, namun saat ini telah
menunjukkan peranannya dalam pengembangan padi. Sentra produksi padi di Maluku terdapat
pada empat kabupaten (Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur),
dengan total luas areal panen pada tahun 2008 sekitar 12.719,5 ha dan produksi 49.954,1 ton,
sedangkan pada tahun 2010 luas areal panen meningkat menjadi 17.779 ha dan produksi 77.532
ton (BPS Maluku, 2011). Meskipun telah terjadi peningkatan produksi, namun produksi tersebut
belum mampu mensuplai kebutuhan beras penduduk Maluku sehingga sabagian besar kebutuhan
beras Maluku masih didatangkan dari luar.
Kecamatan Waeapo (dataran Waeapo), Kabupaten Buru merupakan sentra produksi padi
sawah terbesar di Provinsi Maluku (Susanto & Sirappa, 2007). Kontribusi produksi padi sawah di
Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian 1413
Banjarbaru, 20 Juli 2016
kabupaten Buru pada Tahun 2008 mencapai 70,21 % atau 35.075 ton terhadap total produksi padi
Maluku sebesar 49.954,1 ton. Produksi padi sawah Kabupaten Buru tersebut diperoleh dari luas
panen 8.292 ha atau 65,19 % dari total luas panen untuk Propinsi Maluku sebesar 12.719,5 ha
(BPS Maluku, 2009).
Awal tahun 2012 ditemukan adanya emas di Gunung Botak desa Dafa dusun Wamsaid
Kecamatan Waeapo, semenjak itu Gunung Botak menjadi salah satu wilayah pertambangan yang
didatangi banyak penambang. Tambang emas di Gunung Botak pulau Buru menjadi harapan baru
bagi masyarakat Buru pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buru namun
belum adanya kesepakatan dan ketegasan mengenai aturan penambangan emas di Gunung Botak
oleh pemerintah daerah membuat wilayah Gunung Botak menjadi tempat subur bagi penambang
liar. Ribuan penambang datang dari berbagai daerah di Indonesia (Jawa barat, Maluku Utara, Sulut,
Sulsel dan Sultra), sehingga kegiatan penambangan dan pengolahan emas menjadi tidak terkendali,
hampir pada setiap desa (wilayah pertanian) terdapat tempat tempat pengolahan emas. Para
penambang tidak memperdulikan bahaya dari penggunaan bahan2 kimia (mercuri) terhadap
lingkungan setempat, limbah dari pengolahan dibuang melalui saluran saluran air yang ada didesa,
penduduk desa pun tidak menyadari akan bahaya yang mengancam di kemudian hari, sehingga
sampai pada saat ini kegiatan pengolahan banyak dilakukan di wilayah pertanian.
Bertolak dari urauan tersebut diatas, kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengidentifikasi dampak penambangan emas terhadap aspek social ekonomi dan lingkungan
pertanian .
Metodologi
Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buru, pada Tahun 2013. Petani responden yang
dilibatkan pada penelitian ini adalah petani padi sawah irigasi di Kecamatan Waeyapo, kabupaten
Buru.
Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh
melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan digunakan
metode pemahaman pedesaan secara partisipatif secara terseleksi. Data dimaksud meliputi
karakteristik usahatani, struktur pendapatan/pengeluaran, persepsi petani terhadap kegiatan
penambangan dan kendala yang dihadapi petani dalam berusahatani. Jumlah petani yang menjadi
responden ditentukan secara purposive sampling yang terdiri dari 60 orang petani. Sebagai data
pelengkap dilakukan pengumpulan data sekunder dari Kantor Desa, Dinas Pertanian dan informasi
kunci dari PPL setempat.
Metode Analisis
Analisis data dilakukan untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan kuantitatif
dampak penambangan emas terhadap kegiatan usaha pertanian dan produksi pertanian. Analisa
kualitatif dilakukan dengan mensintesa atau memadukan informasi sehingga terbentuk suatu
kesimpulan yang selaras. Analisis kuantitatif meliputi Analisis finansial usaha tani padi sawah
sebelum dan sesudah adanya tambang
1414 Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian
Banjarbaru, 20 Juli 2016
Hasil dan Pembahasan
Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru
Usaha pertambangan emas di wilayah Buru telah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu,
setelah penemuan urat-urat kuarsa mengandung emas di Desa Dafa dan sekitarnya oleh
penambang emas tradisional dari desa setempat. Kegiatan penambangan emas ini banyak
dilakukan oleh penambang yang berasal dari luar Kabupaten Buru bahkan dari luar Provinsi
Maluku antara lain dari Tasikmalaya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Ternate dan daerah
lainnya, Penambangan dilakukan dengan sistem tambang bawah tanah dengan cara membuat
terowongan (adit) dan sumur (vertical shaft). Teknik penambangan dilakukan tanpa perencanaan
yang baik dan dengan cara penggalian mengikuti arah urat kuarsa yang diperkirakan memiliki
kadar emas cukup tinggi. Pembuatan lubang dilakukan dengan tinggi sekitar 1 meter dan
kedalaman yang bervariasi hingga mencapai ratusan meter. Arah lubang tersebut berupa horizontal
dan vertikal berdasarkan atas penyebaran arah urat kuarsa. Lubang-lubang vertikal di lokasi
kegiatan ini dipergunakan sebagai pintu masuk serta sebagai lubang ventilasi untuk memasukkan
udara dengan bantuan mesin pompa udara. Material yang mengandung bijih emas oleh penambang
di bawa turun dari gunung botak untuk diolah di desa desa sekitar.
Tidak adanya aturan hukum yang khusus mengatur kegiatan pertambangan di Gunung
Botak, serta tidak adanya prosedur administrasi yang harus dilakukan untuk mengatur kegiatan
para penambang tersebut mengakibatkan penambang liar selalu bertambah setiap waktu.
Prakiraan Dampak Lingkungan Tambang Emas Rakyat Di Kabupaten Buru
Pengolahan bijih emas dengan teknik amalgamasi di Kabupaten Buru umumnya hampir
dilakukan di duseluruh desa2 di kecamatan Waeyapo dengan mengambil material dari lokasi
tambang (desa Dafa). proses pengolahan dikerjakan di halaman rumah atau di pinggir sungai
dengan menggunakan tromol. Satu lokasi pengolahan bijih menggunakan 1 10 gelundung tromol
dan setiap gelundung dapat mengolah 15 - 25 kg bijih dalam sehari. Bijih yang telah ditumbuk
dimasukkan kedalam gelundung berisi potongan besi (rod), ditambahkan air, merkuri dan semen,
dan selanjutnya diputar selama 8 - 24 jam dengan tenaga listrik (generator). Setelah proses
amalgamasi selesai, amalgam dipisahkan dari tailingnya dengan cara diperas dengan kain parasit
dan tailing dialirkan ke dalam bak penampungan tailing atau dibiarkan mengalir ke halaman rumah.
Di beberapa lokasi, material tailing yang telah memenuhi kolam dijual dan dibawa keluar untuk
diproses ulang. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan kontaminasi merkuri di lokasi pengolahan
dapat berkurang. Tetapi kadang-kadang dalam kondisi bak penampungan yang telah penuh, proses
pengolahan masih berlangsung sehingga tailing meluap dan mengalir ke halaman atau sungai
kecil/saluran air yang mengalir ke saluran irigasi, terutama jika terjadi hujan, sehingga terjadi
kontaminasi merkuri di lingkungan sekitarnya. Selain itu jika gelundung diletakkan di pinggir
sungai, biasanya tailing dibuang langsung kedalam sungai sehingga kontaminasi merkuri di sungai
akan terjadi secara langsung.
Proses pemisahan emas dari amalgam dilakukan dengan cara penggarangan yang
sederhana tanpa mempertimbangkan kualitas kesehatan dan lingkungan kerja. Amalgam
dimasukkan kedalam mangkok keramik, ditambahkan boraks dan langsung dibakar pada suhu
300-400 C sampai menghasilkan bullion. Proses ini dilakukan di ruangan terbuka sehingga
Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian 1415
Banjarbaru, 20 Juli 2016
merkuri akan langsung menguap dan mengkontaminasi udara di sekitarnya yang merupakan
daerah pertanian padi sawah dan hortikultura. Uap merkuri dapat terhisap dan di dalam tubuh uap
tersebut akan terdifusi melalui paru-paru, yang selanjutnya menyebar melalui darah dan
diakumulasikan di ginjal, hati dan otak yang akhirnya dapat merusak sistem pusat saraf otak.
Untuk mengetahui tingkat kontaminasi cemaran logam berat (merkuri dan timbal)
terhadap lingkungan, telah dilakukan uji laboratorium oleh Badan Ketahanan Pangan bekerja sama
dengan Balai Besar Pasca Panen dengan sampel sayuran, buah dan padi/beras pada beberapa
lokasi yang jauh maupun yang dekat dengan tambang. Ambang batas cemaran logam berat diatur
dalam SNI 7387:2009 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan dan peraturan
Kepala BPOM Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 tentang penetapan batas maksimum
cemaran mikroba dan kimia dalam makanan disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Nilai ambang batas cemaran Pb, Hg.
Komoditas Pb (ppm) Hg(ppm) Referensi
Sayur 0,5 0,03 SNI 7387: 2009
Buah 0,5 0,03 SNI 7387: 2009
Beras (Serealia) 0,3 0,05 SNI 7387: 2009
Beras (Serealia) 0,3 Tidak ad ketentuan Peraturan Kepala
BPOM
Sumber: Badan POM
Cemaran Logam Berat dan Sianida
Hasil analisis cemaran logam berat dicantumkan dalam Tabel 2. Diantara sampel yang
dianalisis, cemaran logam berat Pb yang melebihi ambang batas ketentuan yang berlaku ditemukan
pada komoditas kangkung. Kadar Pb berada pada ambang batas yang berlaku ditemukan pada
sampel sawi, kacang dan semangka. Cemaran Pb pada komoditas beras berada dibawah ambang
batas yang ditetapkan oleh SNI maupun peraturan BPOM yang berlaku.
Untuk cemaran Hg yang berada dibawah ambang batas ditemukan pada sampel jeruk.
Sedangkan pada sampel lainnya, kadar cemaran Hg melebihi ambang batas dari ketentuan yang
berlaku. Cemaran tersebut tidak terdeteksi pada komoditas beras yang berasal dari Debowae,
sedangkan kadar HCN tidak terdeteksi pada semua sampel yang dianalisis.
Tabel 2. Kadar Pb, Hg dan HCN pada beberapa jenis sampel sayuran, buah dan beras di
Kabupaten Buru Tahun 2013.
Pb Hg HCN
No Contoh Lokasi
(ppm) (ppm) (ppm)
1. No. Sampel 5, Komoditas Kangkung Air Panas 0,8 0,2 ttd
2. No. Sampel 5, Komoditas Sawi Waekasar 0,3 0,1 ttd
3. No. Sampel 5, Komoditas Kacang Savana Jaya, 0,3 0,2 ttd
panjang Mako
4. No. Sampel 5, Komoditi Jeruk Wamsait 0,2 0,02 ttd
5. No. Sampel 5, Komoditas Semangka Mako 0,3 0,2 ttd
6. No. Sampel 5, Komoditas Beras Waekasar ttd 0,3 ttd
7. No. Sampel 5, Komoditas Beras Savana Jaya 0,0 0,2 ttd
8. No. Sampel 5, Komoditas Beras Waegeren 0,1 0,2 ttd
9. No. Sampel 5, Komoditas Beras Unit 17 (Parbulu) 0,0 0,2 ttd
10. No. Sampel 5, Komoditas Beras Unit 0,01 ttd ttd
18(Debowae)
Sumber: Badan Ketahanan Pangan (hasil uji Lab, BB pasca panen) Kabupaten Buru
1416 Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian
Banjarbaru, 20 Juli 2016
Residu Pestidida
Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa jenis residu pestisida ditemukan didalam komoditas
kangkung, sawi, jeruk dan beras. Nilai residu pestisida didalam sampel yang dianalisis berada
dibawah ambang batas yang ditetapkan. Hasil analisis disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Kadar residu pestisida pada beberapa jenis sampel sayuran, buah dan beras di Kabupaten
Buru Tahun 2013.
Ketentuan
Konsentrasi
No Contoh Lokasi Kelompok-Jenis SNI
(ppm)
7313:2008
1 No. Sampel 5, Air Panas ORGANOFOSFAT 0,0147 3 ppm
Kom. (Melation)
Kangkung
2 No. Sampel 5, Waekasar ORGANIKLORIN 0,0138 0,05 ppm
Kom. Sawi (Heplaktor Ep) 0,0116 1
ORGANOFOSFAT 0,0160 -
(Profenofos)
KARBAMAT (Karbaril)
3 No. Sampel 5, Savana ORGANIKLORIN (Lindan) 0,0101 0,1
Kom. Kacang Jaya dan ORGANOFOSFAT 0,0150 -
panjang Mako (Metidation)
4 No. Sampel 5, Wamsait ORGANOFOSFAT 0,0105 2
Komoditi Jeruk (Metidation) 0,0091 2
PIRETROID(Sipemetrin)
5 No. Sampel 5, Mako - - -
Kom.
Semangka
6 No. Sampel 5, Waekasar ORGANOFOSFAT 0,0086 0,5
Kom. Beras (Klorpirifos)
7 No. Sampel 5, Savana - - -
Komoditas Jaya
Beras
8 No. Sampel 5, Waegeren ORGANOFOSFAT 0,0072 1
Komoditas (Profenofos)
Beras
9 No. Sampel 5, Unit 17 ORGANIKLORIN (Dieldrin) 0,0061 0,02
Komoditas (Parbulu)
Beras
10 No. Sampel 5, Unit 18 - - -
Komoditas (Debowae)
Beras
Sumber: Badan Ketahanan Pangan (hasil uji Lab, BB pasca panen) Kabupaten Buru
Nilai cemaran Pb dan Hg bervariasi tergantung pada jenis sampel. Cemaran Pb pada
sampel beras dan cemaran Hg pada sampel jeruk berada dibawah ambang batas yang diijinkan
pada SNI 7387:2009, sedangkan cemaran Pb pada kangkung dan cemaran Hg pada beberapa
komoditas beras, buah dan sayur lainnya melebihi ambang batas standar.
Beberapa residu pestisida terdeteksi didalam sampel kangkung, sawi, kacang panjang,
jeruk dan beras, namun residu tersebut masih berada dibawah batas maksimum residu pestisida
sebagaimana ditetapkan didalam SNI 7313:2008. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian 1417
Banjarbaru, 20 Juli 2016
wilayah di sekitar tempat pengolahan emas rakyat telah mengalami kontaminasi merkuri yang
signifikan.
Prakiraan Dampak Aspek Sosio-Ekonomi Tambang Emas Rakyat Di Kabupaten Buru
Dampak sosial ekonomi merupakan dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosial
ekonomi yang dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif akibat aktivitas pertambangan
diantaranya adalah terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terciptanya lapangan
pekerjaan, dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat adat di sekitar wilayah pertambangan
sedangkan dampak negatif dari adanya aktivitas pertambangan antara lain :
1. Terjadinya penurunan pendapatan bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, karena
menurunnya kualitas lahan yang digunakan, meningkatnya biaya tenaga kerja karena
kelangkaan tenaga kerja disektor pertanian.
Analisis finansial usahatani padi sawah sebelum adanya tambang dan setelah adanya tambang
disajikan pada tabel 4.
Hasil analisis finansial usahatani padi sawah sebelum adanya tambang tahun 2011 diperoleh
hasil R/C rasio atas biaya tunai sebesar 1,69 dan R/C rasio atas biaya total sebesar 1,44.
Indeks R/C rasio tersebut menunjukkan bahwa secara finansial usaha tani padi sawah
sebelum adanya tambang masih menguntungkan (layak secara finansial), dengan tingkat
keuntungan Rp. 5.309.184, jika sewa lahan diperhitungkan kedalam biaya maka tingkat
keuntunga RP. 3.959.184. Hasil analisis finansial usahatani padi sawah setelah adanya
tambang tahun 2012 diperoleh hasil R/C rasio atas biaya tunai sebesar 1,11dan R/C rasio atas
biaya total sebesar 1,00. Indeks R/C rasio tersebut menunjukkan bahwa secara finansial usaha
tani padi sawah setelah adanya tambang sudah tidak menguntungkan (tidak layak secara
finansial), dengan tingkat keuntungan Rp.1.296.684, jika sewa lahan diperhitungkan kedalam
biaya maka petani merugi.
Tabel 4. Analisis Finansial Usahatani Padi Sawah Sebelum dan Sesudah adanya Tambang di
kabupaten Buru.
Sebelum adanya Setelah adanya
Komponen Biaya dan Pendapatan tambang tambang
Nilai (Rp) Nilai (Rp)
A. Komponen biaya (Rp/ha/musim)
A.1. Biaya Tetap
- Sewa lahan 1.350.000 1.350.000
A.2. Biaya Variabel
- biaya tenaga kerja 5.475.000 9.225.000
- biaya bahan 1.719.681 1.719.681
A.3. Total biaya diluar bunga 8.544.681 12.294.681
A.4. Bunga modal (10%x biaya tunai
466.968 729.468
prapanen)
A.5. Biaya tunai 7.661.650 11.674.150
A.6. Biaya Total 9.011.650 13.024.150
B. Produksi (kg) 3.243 3.243
C. Penerimaan (Rp) 12.970.833 12.970.833
D. Keuntungan
Keuntungan finansial atas biaya tunai 5.309.184 1.296.684
Keuntungan finansial atas biaya total 3.959.184 -53.316
1418 Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian
Banjarbaru, 20 Juli 2016
Sebelum adanya Setelah adanya
Komponen Biaya dan Pendapatan tambang tambang
Nilai (Rp) Nilai (Rp)
E. Indikator Kelayakan finansial
R/C rasio biaya tunai 1,69 1,11
R/C rasio biaya total 1,44 1
F. Analisis BEP/Titik impas
Titik Impas Produksi (kg) 1.915 2.919
Titik Impas Harga (Rp) 2.363 3.600
Sumber: Data Primer Diolah
Tingkat keuntungan atas biaya tunai dan biaya total disajikan pada gambar 1 dan 2.
14.000.000,00
12.000.000,00 Sblm ad tambang
Stlah ad tambang
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
-
Penerimaan Total Biay a Keuntungan
Gambar 1. Tingkat Keuntungan atas Biaya Tunai
14.000.000,00
Sblm ad tambang
12.000.000,00
Stlah ad tambang
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
Penerimaan Total Biay a Keuntungan
Gambar 2. Tingkat Keuntungan atas Biaya Total
Menurunnya tingkat pendapatan usahatani padi sawah setelah adanya tambang disebabkan
karena naiknya upah tenaga kerja, kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian akibat beralih
pada kegiatan penambangan memicu meningkatnya upah tenaga kerja seperti yang tersaji
pada tabel 5.
Tabel 5. Perkembangan Upah Tenaga Kerja pada Usahatani Padi sawah di Kabupaten Buru
Tahun
Jenis Kegiatan 2011 2012 2013 % Perubahan
Tenaga kerja harian (Rp) 50.000 90.000 100.000 100
Tanam (borongan) (Rp/ha) 525.000 750.000 1.000.000 90
Olah tanah/sewa traktor (Rp/ha) 800.000 1.100.000 1.475.000 84
Sewa Dores (Rp/ha) 275.000 375.000 512.500 86
Sumber: Data Primer Diolah
Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian 1419
Banjarbaru, 20 Juli 2016
Upah tenaga kerja harian (kegiatan mencangkul, memupuk, menyiang dan pamanenan,)
meningkat 100% setelah adanya tambang sedangkan upah untuk tanam pindah dengan sisitem
borongan meningkat 90% dari harga semula sebelu adanya tambang. Biaya olah tanah atau
sewa traktot meningkat 84% dan sewa dores meningkat 86% setelah adanya penambangan.
2). Terjadinya peningkatan kebutuhan sembako karena banyaknya penduduk dari luar sebagai
penambang dan meningkatnya harga harga sembako.
Sejak ditemukannya emas di Gunung Botak desa Dafa pada pertengahan tahun 2012, Gunung
Botak menjadi salah satu wilayah pertambangan yang didatangi banyak penambang dari
berbagai daerah di Indonesia. Adanya ribuan penambang yang silih berganti datang ke pulau
Buru menyebabkan kebutuhan pangan di Kabupaten Buru meningkat sehingga menjadikan
peluang bagi para pedagang untuk mendatangkan komoditas pangan dari luar Buru, salah
satunya yaitu komoditas beras, sejak tahun 2012 berbagai merk dagang beras masuk ke
kabupaten Buru
Besarnya permintaan terhadap komoditas pangan (sembako) sedangkan ketersediaan terbatas
menyebabkan harga harga sembako meningkat cukup tinggi, sehingga pendapatan riil
masyarakat sekitar tambang (petani) menurun. Peningkatan harga sembako berkisar antara 8%
sampai 30% dengan rata-rata 17,6%.
Prakiraan Dampak Terhadap Aspek Keamanan Akibat Adanya Tambang Emas Rakyat Di
Kabupaten buru
Tidak adanya aturan hukum yang khusus mengatur kegiatan pertambangan di Gunung Botak,
serta tidak adanya prosedur administrasi yang harus dilakukan untuk mengatur kegiatan para
penambang tersebut mengakibatkan penambang liar selalu bertambah setiap waktu. Dari sisi
keamanan, sering terjadi bentrokan antar warga asli dan warga pendatang yang menewaskan
beberapa penambang. Tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah pertambangan yang
penyelesaiannya tidak dilakukan secara tuntas membuat kekhawatiran masyarakat sekitar. Terjadi
perkelahian antar orang gunung pemilik tanah ulayat, meningkatnya pencurian di rumah-rumah
warga terutama yang memiliki banyak emas, mengakibatkan masyarakat setempat menjadi resah.
Masuknya para penambang dari luar Kabupaten Buru menjadikan kondisi desa-desa disekitar area
pengolahan menjadi tidak aman, penduduk setempat menjadi khawatir.
Prakiraan Dampak Terhadap Aspek Kesehatan Akibat Adanya Tambang Emas Rakyat Di
Kabupaten buru
Maraknya jasa pelayanan seksual di lokasi tambang menjadikan masyarakat disekitar
khawatir akan munculnya virus mematikan HIV/AIDS yang dibawa oleh para pekerja seks
komersial (PSK). Limbah mercury yang sudah diluar ambang batas toleransi akan memberikan
dampak buruk bagi kesehatan secara luas terhadap masyarakat Kabupaten Buru, terlebih khusus
lagi mereka yang terkontaminasi limbah tersebut. Uap mercury pada proses penggarangan dapat
terhisap dan di dalam tubuh uap tersebut akan terdifusi melalui paru paru, yang selanjutnya
menyebar melalui darah dan diakumulasikan di ginjal, hati dan otak yang akhirnya dapat merusak
sistem pusat. Terbatasnya ketersediaan air bersih dilokasi tambang menyebabkan banyak para
penambang yang menderita penyait kulit.
1420 Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian
Banjarbaru, 20 Juli 2016
Kesimpulan
Kehadiran pertambangan emas di kabupaten Buru pada umumnya memberikan dampak
negatif pada aspek sosio-ekonomi dan ekologi. Pada aspek sosio-ekonomi, terjadinya penurunan
pendapatan usahatani karena meningkatnya biaya produksi, kelangkaan tenaga kerja dibidang
pertanian karena sebagian besar beralih pada kegiatan tambang sehingga memicu kenaikan upah
tenaga kerja, keterbatasan dan meningkatnya harga-harga sembako, tingginya komoditas beras dari
luar yang masuk ke pulau buru sehingga mempengaruhi pemasaran beras lokal.
Pada aspek sosio- ekologi, yaitu terjadinya pencemaran lingkungan. Proses pengolahan
emas berada di halaman rumah dan kebun, memungkinkan terjadinya pencemaran merkuri
terhadap lingkungan hidup, terutama jika kolam penampungan tailing tidak ditangani dengan baik.
Selain itu proses penggarangan secara sederhana dilakukan di sekitar rumah, dapat menyebabkan
pencemaran lingkungan oleh uap merkuri yang ditimbulkannya. Penanganan tailing (limbah)
dilakukan secara sederhana dengan kolam penampungan yang sangat terbatas, tanpa disertai
dengan pengelolaan yang baik, seperti misalnya tidak dilakukannya proses detoksifikasi, degradasi,
maupun penjernihan, sehingga material halus merkuri, arsen dan logam dasar masih bercampur
dalam tailing. Oleh karenanya disarankan untuk melakukan penanganan tailing dengan cara daur
ulang dan dengan sistem kolam penampungan yang lebih memadai. Selain itu pengangkutan atau
penjualan material tailing keluar daerah secara teratur dapat mengurangi pencemaran merkuri di
daerah Sangon dan sekitarnya.
Pengolahan emas dengan teknik amalgamasi telah menyebabkan kontaminasi merkuri
pada lingkungandi sekitarnya. Hasil analisis kimia terhadap sampel hasil pertanian menunjukkan
adanya kontaminasi merkuri dan logam berat diatas ambang batas. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan dampak lingkungan yang negatif dan berbahaya bagi masyarakat di wilayah
Kabupaten Buru. Dari Aspek keamanan, sering terjadi bentrokan antara warga asli dan warga
pendatang yang menewaskan beberapa penambang, tingginya tingkat pencurian yang meresahkan
masyarakat.
Kondisi lingkungan yang tercemar akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat secara
perlahan2 dan dalam jangka panjang dikhawatirkan akan terjadi tragedi seperti kasus teluk Buyat
atau teluk minamata.
Daftar Pustaka
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru 2013. Hasil Uji Laboratorium Cemaran Logam Berat
dan Cianida pada Komoditas Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Burut. Badan
Ketahanan Pangan - Namlea.
BPS Maluku., 2011. Maluku Dalam Angka. BPS Provinsi Maluku, Ambon
BPS Maluku., 2009. Maluku Dalam Angka. BPS Provinsi Maluku, Ambon
Bustaman, S dan A.N. Susanto., 2003. Potensi Lahan Beserta Alternatif Komoditas Pertanian
Terpilih Berdasarkan Peta Zona Agroekologi pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Buru.
Balai pengkajian Teknologi Pertanian Maluku, Ambon.
Djaenudin., 1998. Penataan Ruang Berdasarkan Sumberdaya Lahan Mendukung Pewilayahan
komoditas Pertanian (Studi Kasus Propinsi Sulawesi Tenggara) Dalam Jurnal Penelitian
dan Pengembangan Pertanian, vol.XVII, 1:23-31
Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian 1421
Banjarbaru, 20 Juli 2016
Irianto, B, S. Buataman, A.N. Susanto, A.J. Riewpassa dan E.D. Waas., 1998. Baseline Data
biostik dan Sosial Ekonomi pada Delapan Gugus Pulau di Provinsi maluku. Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku, Ambon
Sujai, M., 2011. Dampak Kebijakan Fiskal Dalam Upaya Stabilitas Harga Komoditas Pertanian.
Dalam Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ,
Vol.9, No.4:297-392
Noor, D. 2006. Geologi Lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Susilo, Y.E.B., 2003. Menuju Keselarasan Lingkungan. Averroes Press, Malang, 156 hal.
Veronika S.A.,2009 dalam Mohammad Ahyani, 2011. Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas
Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat Di Bombana
Provinsi Sulawesi Tenggara, Thesis, Program Magister Ilmu Lingkungan Program
Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
1422 Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian
Banjarbaru, 20 Juli 2016
Anda mungkin juga menyukai
- Hainunnnn Baru Desember Revisi Ujian 1Dokumen56 halamanHainunnnn Baru Desember Revisi Ujian 1Deejay ShanellBelum ada peringkat
- Rumah KacaDokumen660 halamanRumah KacaDeejay ShanellBelum ada peringkat
- Rps Sos Perkotaan Format Baru-MinDokumen27 halamanRps Sos Perkotaan Format Baru-MinDeejay ShanellBelum ada peringkat
- Makalah Maritim Ekonomi MaritimDokumen26 halamanMakalah Maritim Ekonomi MaritimDeejay ShanellBelum ada peringkat
- WIRA EDISI KHUSUS Fix A4Dokumen86 halamanWIRA EDISI KHUSUS Fix A4Deejay ShanellBelum ada peringkat
- Mentor Pend Bela NegaraDokumen9 halamanMentor Pend Bela NegaraDeejay ShanellBelum ada peringkat