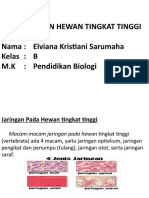Buku 5 Pengembangan Desa Rev
Buku 5 Pengembangan Desa Rev
Diunggah oleh
Hanif ShonenHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Buku 5 Pengembangan Desa Rev
Buku 5 Pengembangan Desa Rev
Diunggah oleh
Hanif ShonenHak Cipta:
Format Tersedia
PENGEMBANGAN
DESA
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Kasanah Implementasi UU Desa
PENGEMBANGAN
DESA
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia i
ii Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
PENGEMBANGAN
DESA
November 2015
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia iii
Pengembangan Desa
PENGARAH : Ahmad Erani Yustika (Direktur Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
PENANGGUNGJAWAB: Eko Sri Haryanto (Direktur
Pemberdayaan Masyarakat Desa)
PEMBACA : Bito Wikantosa (Kepala Subdirektorat
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa).
Cover & Lay Out : Heru YP
Ilustrtor : Ibe Karyanto
Cetakan Pertama – November 2015
Diterbitakan Oleh :
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Jl. TMP Kalibata, No 17, Jakarta Selatan – 12740
Telp (021) 7989924
iv Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
DAFTAR ISI
Bagian 1
Desa Mandiri, Desa Membangun 1
Bagian 2
Badan Usaha Milik Desa :
Spirit Usaha Kolektif Desa 17
Bagian 3
Kerja Sama Desa :
Mengembangkan Jaringan Sosial
Dan Kemitraan 29
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia v
PENGANTAR
Sepantasnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, karena dengan rahmatNya telah diselesaikan
beberapa seri penerbitan beberapa buku yang diperlukan untuk
kelengkapan pelatihan yang bertujuan mengintensifkan kerja-
kerja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Salah
satunya adalah penerbitan buku Pengembangan Desa Desa
yang melekapi kasanah pengetahuan Implementasi Undang-
undang Desa. Buku yang sekarang di tangan pembaca ini
menyajikan tiga tema substansial terkait dengan pengembangan
Desa. Masing-masing adalah Desa Mandiri; Desa Membangun,
Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Usaha Desa, dan
Kerja Sama: Mengembangkan Jaringan Sosial dan Kemitraan.
Desa Membangun merupakan salah satu spirit Desa yang
terbangun oleh azas pengakuan hak asal-usul dan kewenangan
Desa yang dimandatkan UU Desa. Frasa Desa Membangun
menunjukkan eksistensi Desa sebagai subyek, pelaku utama
pembangunan. Keberadaan Desa sebagai subyek mendapatkan
ruang gerak yang semakin nyata dalam Nawa Cita yang
menjadi visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara.
Buku ini memberikan acuan yang cukup memadai
untuk bisa memahami tema substansial tersebut di atas.
Pembagian substansi tematik ke dalam bab-bab yang terpisah,
serta penjelasan yang ringkas dengan langsung memaparkan
substansi persoalan memudahkan bagi setiap pembaca.
Diharapkan tenaga profesional pendampingan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik Tenaga
vi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa maupun
Setrawan membaca dan memahami dengan baik isi buku ini. Buku
kecil ini juga bermanfaat bagi siapa pun, pegiat implementasi UU
Desa, baik perangkat Desa, masyarakat Desa maupun unsur lain.
Akhir kata, terlepas dari berbagai kekurangan
maupumn kelemahan yang ada, semoga buku bermanfaat
menambah kasanah kepustakaan buku-buku dan
bacaan sekitar implementasi UU Desa khususnya serta
memperkaya perspektif pembaca dalam melakukan upaya
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Selamat belajar dan selamat menggunakan buku ini dengan bijak.
Direktur Jenderal
Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Ahmad Erani Yustika
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia vii
Bagian Satu
Desa Mandiri,
Desa Membangun
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 1
PENGANTAR
A. PARADIGMA DAN KONSEP DESA
Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa
secara nasional. UU ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar
belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU itu juga
mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas
rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan Desa. Lebih daripada
itu, UU Desa telah mengangkat hak dan kedaualatan Desa yang
selama ini terpinggirkan. Semua itu tertangkap secara eksplisit
dengan menyimak ketentuan Pasal 4 UU No.6/ 2014 mengenai tujuan
pengaturan Desa.
Secara kontras, UU Desa telah memberikan landasan perspektif
dalam pengaturan Desa dibanding Undang-Undang sebelumnya (UU
No. 5/1979 dan UU No. 32/2004) beserta peraturan perundangan
turunannya. Perbandingan antara pengaturan Desa pada UU No.
32/2004 dan UU No. 6/2014 dapat disimak dalam tabel 1 di bawah ini.
Secara umum, UU Desa meletakkan Desa dalam posisi
selayaknya, yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum khas
Indonesia yang keberadaannya mendahului Negara modern
Indonesia. Selain itu juga pengakuan atas kewenangan berdasar
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang
memberikan keleluasaan bagi Desa untuk menyelenggarakan
Pembangunan Desa secara mandiri.
2 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Tabel 1
Kerangka & Praktek Desa Sebelum UU Desa dan Desa dalam
Perspektif UU Desa
ASPEK SEBELUM UU DESA DESA DALAM UU DESA
PAYUNG HUKUM UU No. UU NO. 6/2014,
32/2004,
PP No. 43/2014,
PP No.
72/2005. PP No. 60/2014,
PP No. 47/2015,
PP No. 22/2015.
ASAS UTAMA Desentralisasi-resid- Rekognisi-subsidiaritas
ualitas
KEDUDUKAN Sebagai organisasi Sebagai pemerintahan mas-
pemerintahan yang yarakat, campuran antara mas-
berada dalam sistem yarakat yang berpemerintahan
pemerintahan Kabu- (self governing community) dan
paten/Kota (local state pemerintahan lokal (local state
government) government).
POSISI DAN PER- Kabupaten/Kota mem- Kabupaten/Kota mempunyai
AN KABUPATEN/ punyai kewenangan kewenangan yang terbatas
KOTA yang besar dan luas dan strategis dalam mengatur
dalam mengatur dan dan mengurus Desa; termasuk
mengurus Desa mengatur dan mengurus bidang
urusan Desa yang tidak perlu
ditangani langsung oleh Pusat.
DELIVERY KE- Target Mandat
WENANGAN DAN
PROGRAM
POLITIK TEMPAT Desa sebagai lokasi Desa sebagai arena bagi orang
proyek dari Pemerin- Desa untuk menyelenggarakan
tah Daerah/Pemerin- pemerintahan, pembangunan,
tah Pusat pemberdayaan, dan kemas-
yarakatan
POSISI DESA Obyek/penerima Subyek/pelaku pembangunan
DALAM PEMBAN- manfaat
GUNAN
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 3
MODEL PEMBAN- Pembangunan diren- Desa menyelenggarakan
GUNAN canakan Pemerintah pembangunan (perencanaan,
Daerah/Pemerintah pelaksanaan, evaluasi)
Pusat
PENDEKATAN Imposisi dan mutilasi Fasilitasi, emansipasi, dan
DAN TINDAKAN sektoral konsolidasi
Sumber: Sutoro Eko, dkk. Desa Membangun Indonesia (2014)
Tabel di atas menyajikan secara kontras pengaturan Desa
menurut UU No. 32/2014 dengan UU No. 32/2004 beserta peraturan
perundangannya masing-masing. Sangat tampak bahwa UU Desa
telah menjadi langkah maju bagi pembaruan Desa. Dengan kata
lain, pendamping harus benar-benar memahami visi dasar UU
Desa agar visi tersebut dapat diimplementasikan dalam tugas dan
tanggung jawab Pendamping Desa.
B. DESA BERDAULAT DAN MANDIRI
Visi UU Desa dapat ditangkap pula dari jalan ideologis Pemerintah
seperti tercantum dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Nasional) 2015-2019 yang dikenal dengan Trisakti.
Tiga butir dalam Trisakti adalah:
1. Kedaulatan dalam politik;
2. Berdikari dalam ekonomi; dan
3. Berkepribadian dalam kebudayaan.
Pelaksanaan UU Desa secara konsisten membuka peluang dalam
mewujudkan jalan ideologis di atas. Sebagai kesatuan masyarakat
hukum terdasar dan terdepan, men-support visi UU Desa adalah sama
dengan mengembangkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan
berkepribadian.
PERTAMA, dari UU Desa, berdaulat secara politik dapat difahami
bahwa desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengatur
4 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
dan mengurus dirinya. Pada dasarnya, Desa bahkan memiliki tradisi
permusyawaratan dimana keterbukaan dan partisipasi menjadi pilar
dalam pengambilan keputusan. Pemilihan kepala desa secara langsung
telah menjadi tradisi desa dalam berdemokrasi.
KEDUA, kemandirian ekonomi Desa merupakan aspek penting
dari UU Desa. Melalui UU Desa, kemandirian ekonomi dirintis melalui
pengelolaan aset Desa yang dipayungi oleh kewenangan berdasar hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
KETIGA, pengakuan terhadap hak asal usul Desa (rekognisi) dalam
UU Desa memberi jalan bagi perjumpaan kreatif antara tradisi budaya
lokal dengan inovasi-inovasi baru. Artinya, segala sesuatu yang berasal
dari luar dikembangkan dengan cara atau tradisi yang berkembang di
Desa. Semua itu merupakan fase paling mendasar dalam pembentukan
identitas budaya tanpa terpangkas dari dinamika perkembangan dunia
kontemporer.
Dengan kata lain, pembaruan Desa merupakan keniscayaan yang
harus ditempuh melalui UU No. 6/2014 beserta peraturan perundangan
turunannya. Sebagaimana ditegaskan sebagai tujuan pengaturan Desa
di Pasal 4 huruf i UU No. 6/2014: memperkuat masyarakat Desa sebagai
subjek pembangunan. Desa, yaitu Pemerintah Desa dan masyarakat
Desa, menjadi subjek pembangunan atau: Desa membangun Indonesia.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 5
1. DESA MEMBANGUN
A. MEMBANGUN DESA
Konsep pembangunan di Indonesia sejatinya berkait dengan
konsep developmentalisme yang dikembangkan negara-negara barat
dan dipraktekkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Istilah ini sering
dipakai untuk menunjuk perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi,
modernisasi dan rekayasa sosial. Dalam konteks pemerintahan
Orde Baru, implementasi konsep pembangunan meletakkan Desa
sebagai obyek pembangunan, yaitu pihak yang hanya menerima
‘manfaat’ pembangunan; bukan pihak yang menyelenggarakan
pembangunan berdasar kebutuhan dan kepentingan Desa.
Dalam posisi tersebut Desa tidak lebih hanya menjadi lokasi
program pembangunan Pemerintah. Masalahnya, program
pembangunan itu dirumuskan berdasar analisis atau pembacaan
dari Pemerintah, bukan dirumuskan berdasar kebutuhan dan
kepentingan Desa atau apalagi dirancang oleh masyarakat Desa.
Artinya kapasitas masyarakat Desa untuk menganalisis keadaan
Desanya, merumuskan kebutuhan, membuat perencanaan
pembangunan, melaksanakan pembangunan, hingga mengevaluasi
pembangunan Desanya, tidak pernah meningkat. Ibarat masakan,
masyarakat Desa tidak pernah diberi kesempatan untuk memasak,
melainkan hanya menerima masakan yang sudah matang sehingga
kemampuan memasak masyarakat Desa tidak mengalami
perkembangan.
6 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Implementasi cara pandang pembangunan di atas cukup lama,
30 tahun lebih dan akibatnya masih bisa dirasakan sampai saat ini.
Setidaknya akibat yang menonjol adalah dua gejala berikut.
PERTAMA adalah mental ketergantungan Desa pada program-
program pembangunan dari pemerintah, baik Pemerintah
Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun pusat. Kemandirian dan inisiatif
baik Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa tidak terasah
dengan baik.
KEDUA, dengan datangnya program dari pusat, Desa tidak lagi
dipandang sebagai sumber penghidupan, melainkan hanya ‘asal
kehidupan’ atau kampung halaman yang sewaktu-waktu dapat
ditinggalkan. Ditinggalkan ke mana? Ke Kota, tempat yang dianggap
sebagai pusat lapangan kerja atau sumber penghidupan.
Sebab pelaku pembangunan sesungguhnya adalah pemerintah
(Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat) dan Desa hanya menjadi
lokasi pembangunan, yang berlangsung adalah ‘membangun Desa’;
Desa menjadi objek pembangunan atau yang dibangun.
B. DESA MEMBANGUN
UU No. 6/2014 tentang Desa membalik perspektif di atas. menempatkan
desa sebagai subyek pembangunan. Pembalikan itu dapat ditemukan
melalui pengakuan atas hak asal usul Desa (rekognisi) dan kewenangan
lokal berskala Desa (subsidiaritas) yang menjadi dua asas utama
pengaturan Desa.
Dengan kewenangannya, Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan
pembangunan dan pemberdayaan. Agenda pembangunan, mulai
dari perencanaan hingga evaluasi, dilakukan oleh Desa. Sementara,
dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintahan di atas Desa,
Pemerintah Desa juga memiliki tungas pemberdayaan agar kapasitas
masyarakat Desa meningkat. Seluruh agenda pembangunan dan
pemberdayaan harus dirumuskan melalui Musyawarah Desa dan
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 7
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang
wajib melibatkan unsur-unsur masyarakat Desa. Semua itu merupakan
kondisi yang berkebalikan dari praktek pembangunan yang diterapkan
dalam perspektif yang dipaparkan sebelumnya. Tujuan yang diharapkan
dari pola tersebut adalah.
PERTAMA masyarakat dan Pemerintah Desa mampu mengembangkan
inisiatif pembangunan, kemampuan membaca masalah dan kebutuhan
Desa, serta menindaklanjutinya secara sistematis dan operasional
dalam program-program pembangunan Desa.
KEDUA masyarakat Desa dan Pemerintah Desa memiliki kemampuan
mengevaluasi dan mengelola potensi dan aset Desa sebagai sumber
ekonomi Desa yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.
KETIGA, Desa menjadi subjek pembangunan yang tidak lagi tergantung
pada program dari luar Desa. Desa akan semakin mandiri dan berdaya,
sehingga masyarakatnya juga tidak perlu terpesona oleh kesan-kesan
kemudahan hidup di Kota yang sampai saat ini terus menarik laju
urbanisasi.
KEEMPAT, dengan berkembangnya kapasitas Pemerintah dan
masyarakat Desa, beban atau tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/
Kota, Provinsi, dan Pusat dalam tugas-tugas pembangunan langsung
Desa, semakin berkurang. Artinya, Pemerintah dapat mengerahkan
kelebihan energinya untuk urusan-urusan yang lebih strategis.
Cara pandang yang dikembangkan dari UU Desa di ataslah yang disebut
sebagai Desa Membangun, atau dalam skala yang lebih luas dan
nasional, dengan kemandirian dan kapasitasnya, Desa Membangun
Indonesia. Itu semua, bukan ikhwal yang mustahil. Perbandingan antara
dua perspektif tersebut dapat disimak di tabel 2 berikut.
Tabel 2
Perbedaan Konsep
8 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
“Membangun Desa” dan “Desa Membangun”
ITEM/ISU MEMBANGUN DESA DESA MEMBANGUN
Pintu Masuk Kawasan perdesaan Desa
Isu Terkait Jaringan rural-urban, market, Kemandirian, kearifan lokal,
pertumbuhan, infrastruktur, modal sosial, demokrasi,
kawasan, sektoral, dll. partisipasi, kewenangan,
alokasi dana, gerakan
lokal, pemberdayaan, dll.
Skema kelem- Pemda melakukan peren- Regulasi menetapkan
bagaan canaan dan pelaksanaan kewenangan skala Desa,
didukung alokasi dana melembagakan perenca-
khusus. Pusat melakukan naan Desa, alokasi dana,
fasilitasi, supervisi dan dan kontrol lokal
akselerasi.
Pemegang ke- Pemerintah Daerah Desa (Pemerintah Desa dan
wenangan masyarakat Desa)
Tujuan Mengurangi keterbelakangan, 1. Menjadikan Desa sebagai
ketertinggalan, kemiskinan, basis penghidupan dan
sekaligus membangun kes- kehidupan masyarakat
ejahteraan secara berkelanjutan;
2. Menjadikan Desa sebagai
ujung depan yang dekat
dengan masyarakat, serta
Deesa yang mandiri
Peran Pemerin- Merencanakan, membiayai, Fasilitasi, supervisi dan
tah Daerah dan melaksanakan pengembangan kapasitas
Desa
Peran Desa Berpartisipasi dalam peren- Sebagai aktor atau subjek
canaan dalam perencanaan utama yang meren-
dan pengambilan keputusan canakan, membiayai dan
melaksanakan
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 9
Hasil Infastruktur lintas-Desa Pemerintah Desa menjadi
yang lebih baik ujung depan penyeleng-
garaan pelayanan publik
Tumbuhnya kota-kota kecil bagi warga
sebagai pusat pertumbuhan
Satu Desa mempunya
dan penghubung transasksi
ekonomi Desa-Kota produk ekonomi unggulan,
dll.
Terbangunnya kawasan
hutan, pertanian kolektif,
industri, wisata, dll.
10 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
2. TANTANGAN DAN STRATEGI MEWUJUDKAN
DESA MANDIRI
A. TANTANGAN
Tantangan implementasi UU Desa dan mewujudkan Desa mandiri
dapat disimak dari optimisme dan kekhawatiran para pengamat
terhadap pelaksanaan UU Desa sepanjang tahun 2015 ini – tahun
pertama implementasi UU No. 6/2014. Tantangan tersebut di antaranya
adalah sebagai berikut.
PERTAMA terkait kekhawatiran yang berpangkal pada persoalan
Dana Desa yang dikelola desa. Meski semua masih berjalan, ada
kekhawatiran terjadi penyelewengan anggaran publik yang massif di
Desa-desa. Akar masalahnya ada pada kapasitas pemerintah desa
yang masih lemah.Prasangka ini, di satu sisi memang harus diterima
sebagai cermin kewaspadaan dan pelecut motivasi, khususnya bagi
Pemerintah Desa dan Pendamping Desa.
KEDUA merubah sikap pasif masyarakat Desa dalam urusan
pemerintahan ke arah sikap aktif dan kritis. Singkatnya merangsang
partisipasi masyarakat Desa. Pengawasan terhadap penggunaan
Dana Desa dan APBDesa secara keseluruhan hanya akan efektif
apabila dilakukan secara langsung oleh masyarakat Desa. Merekalah
yang mesti menjadi evaluator utama untuk menjadi penyeimbang
kemungkinan terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran publik
oleh Pemerintah Desa.
KETIGA membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah
Desa, sekaligus menjadi jembatan antara Pemerintah Desa dengan
masyarakat Desa. Tantangan ini khususnya berlaku bagi Pendamping
Desa.
KEEMPAT, perhatian publik atas UU Desa secara umum masih
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 11
terpaku pada persoalan Dana Desa. Sementara aspek strategis terkait
visi kemandirian Desa dan visi Desa membangun justru tidak mendapat
perhatian yang cukup.
Semua itu menjadi tantangan pertama bagi mewujudkan Desa
mandiri, atau secara umum dalam upaya implementasi UU Desa. Peran
pendamping, kapasitasnya, pemahaman, dan penguasaan wawasan
terkait UU Desa beserta peraturan perundangan turunannya menjadi
kunci utama dalam menunjukkan bahwa kemandirian Desa yang dicita-
citakan oleh UU Desa adalah mungkin.
B. STRATEGI & LANGKAH MENUJU DESA MANDIRI
Lalu, bagaimana mewujudkan kemandirian desa?.Berkait
dengan pertanyaan ini, sesungguhnya telah banyak desa-desa
yang sudah merintis kemandirian Desa tanpa menunggu kehadiran
pemerintah supradesa. Silakan dicermati desa kita, pasti ada
pertikan-pertikan inovasi lokal yang menunjukkan keberdayaan
dan kemandirian desa. Belajar pada berbagai praktik inovatif
dan emansipatif yang tumbuh dari dalam desa-desa diberbagai
belahan negeri Indonesia, dapat ditarik beberapa strategi yang
semoga layak diterapkan.
12 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
PERTAMA, membangun kapasitas warga dan organisasi
masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses
pembentukan wadah dan organisasi masyarakat sipil biasanya
dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski
demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun
kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang akan
menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang
tidak responsif pada kepentingan masyarakat.
Bagaimana agar wadah dan organisasi kemasyarakatan desa
tersebut memiliki peran membangun desa yang mandiri? Apa yang
sebaiknya dilakukan pemerintah desa di masa depan? Langkah-
langkahnya kurang-lebih:
1. Melakukan assessment dan pemetaan kapasitas
organisasi kemasyarakatan desa. Tujuan lagkah ini adalah untuk
memetakan berapa dan apa saja organisasi kemasyarakatan desa
yang masih aktif dan pasif. Dengan demikian akan tampak organisasi
kemasyarakatan desa yang masih ada struktur organisasinya tapi
sudah tidak ada lagi pengurusnya. Atau masih ada pengurusnya namun
tidak memiliki program dan kegiatan yang jelas. Tujuan selanjutnya
adalah agar Desa memiliki gudang data tentang apa saja masalah
dan potensi yang dimiliki organisasi kemasyarakatan desa sehingga
memungkinkan menjadi mitra strategis Pemerintah Desa dalam
menjalankan mandat pembangunan.
2. Menyelenggarakan program/kegiatan yang berorientasi
pada peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan Desa.
Bentuk kegiatan untuk penguatan kapasitas misalnya pelatihan
managemen organisasi, mendorong restrukturisasi/peremajaan
pengurus organisasi, ataupun pemberian bantuan desa untuk organisasi
kemasyarakatan desa.
3. Pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses-
proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan
pemerintah desa. Setiap kebijakan strategis Desa harus dilandasai
atas musyawarah mufakat semua elemen Desa (Pemerintah Desa
dan masyarakat Desa). Di samping itu salah satu yang menjamin
peran dinamis organisasi masyarakat sipil di desa adalah pelibatan
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 13
mereka ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan
desa. Melalui cara ini, Pemerintah Desa telah mengedepankan
prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam
pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir proses check and
balancies dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
KEDUA, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi
dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. Selain terhadap organisasi kemasyarakatn,
penguatan kapasitas juga harus dilakukan terhadap Pemerintah Desa.
Seperti tantangan yang dikemukakan di atas, yaitu kapasitas Pemerintah
Desa dalam tata kelola keuangan Desa. Namun penguatan kapasitas
tersebut juga harus dibarengi dengan mengembangkan interaksi yang
dinamis anatara Pemerintah Desa dengan organisasi masyarakat.
Maksud interaksi dinamis adalah bahwa seluruh proses berdesa,
urusan publik, dan kebijakan-kebijakan di Desa mesti dilakukan dengan
melibatkan masyarakat Desa.
KETIGA, membangun sistem perencanaan dan penganggaran
desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri
dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang
terarah di ditopang partisipasi warga yang baik. Secara skematik
pembelajaran penerapan sistem tersebut sebagai berikut: (i) melalui
Musrenbang desa Pemerintah Desa mempertemukan visi dan
misi kepala desa terpilih dengan aspirasi dan kebutuhan prioritas
masyarakat lalu memasukannya secara konsisten dalam dokumen
perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa); (ii) Pemerintah Desa
membahas dan memastikan ide atau usulan program mandiri
pangan (pengadaan bibit, dll) masuk dalam dokumen anggaran
(RAPBDesa dan APBDesa); (iii) pemerintah desa memastikan
pelaksanaan kegiatan belanja anggaran seperti pengadaan bibit,
warga menanam, hingga memastikan tanaman yang ditanam benar-
benar tumbuh baik.
KEEMPAT, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang
mandiri dan produktif. Saat ini banyaksekali tumbuh inisiatif desa
membangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan di bidang
ekonomi tersebut tidak lepas dari kemampuan desa membangun
perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa, RKP Desa dan
14 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
APB Desa).
Mewujudkan Desa mandiri bukan pekerjaan yang mudah, namun
bukan mustahil untuk dilakukan dan terwujud. Bagi pendamping
tentu ini bukan tugas sederhana. Akan tetapi, kita harus percaya dan
awas dengan kondisi aktual Desa, yaitu bahwa dalam derasnya arus
pembangunan Desa selama ini, selalu ada kearifan dan inovasi-inovasi
Desa yang membuat Desa memiliki peluang untuk bertahan, sejahtera,
dan mandiri. Bagi pendamping di Desa-desa, inovasi-inovasi Desa itu
sangat penting untuk digali dan tidak boleh luput dari perhatian.
3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Dalam upaya untuk mewujudkan Desa Mandiri seperti yang dicita
citakan, tentunya harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat
desa sebagai pelaku utamanya. Scenario kebijakan dari Kemendesa
PDTT dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat dengan
melalui strategi 3 (tiga) daya : Pertama). Pengembangan lumbung
ekonomi rakyat, Kedua). Penguatan jaring komunitas wiradesa, dan
Ketiga). Pengembangan lingkar budaya Desa.
Rumusan strategi 3 (tiga) daya tersebut dimaknai operasionalisasinya
sebagai berikut:
a. Lumbung Ekonomi Rakyat adalah pengembangan ekonomi
masyarakat Desa sesuai potensi ekonomi desa baik atas
prakarsa masyarakat Desa dan/atau prakarsa Pemerintah
Desa yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan
masyarakat Desa.
b. Jaring Komunitas Wiradesa adalah penguatan kapasitas
masyarakat Desa dalam hal pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, dan kesadaran dalam kehidupan
ekonomi, sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
c. Lingkar Budaya Desa adalah pengembangan budaya,
tradisi, dan kearifan lokal sebagai pengikat solidaritas dan
kegotongroyongan dalam seluruh sektor kehidupan Desa
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 15
Tentunya strategi 3 daya ini bagi pendamping bisa menjadi kerangka
dan persfektif dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat
dalam mendukung dan mewujudkan Desa Mandiri. Tentunya strategi
ini harus diselaraskan dengan kearifan dan inovasi-inovasi Desa untuk
mengebangkan desa mandiri.
PENUTUP
Tulisan ini mungkin belum berhasil menyajikan cara atau tips-
tips sederhana dan jitu bagaimana membangun desa mandiri.
Pemahaman dan strategi yang telah dipaparkan di tiga bab di atas
setidaknya telah menunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan
sekongkrit mungkin.
Catatan terpenting, langkah mewujudkan Desa mandiri harus
diberangkatkan dari kondisi Desa setempat. Artinya keawasan
pendamping dalam menyimak, mencerna, dan bergaul dengan
masyarakat Desa sangat dibutuhkan. Sementara paparan wawasan
dan garis strategi yang telah dipaparkan di atas merupakan panduan
yang bersifat umum untuk diimprovisasikan di lapangan. Semua
itu perlu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Desa membangun
Indonesia, sebuah agenda strategis yang penting dan menentukan
bagi kehidupan bangsa secara nasional.
16 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Bagian 2
BADAN USAHA MILIK DESA:
Spirit Usaha Kolektif Desa
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 17
PENGANTAR
A. Makna BUM Desa
UU No. 6/20014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi
Pemerintahan Jokowi-JK dengan menempatkan posisi Desa sebagai
“kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi
Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan bermartabat. Prioritas tersebut
tercermin dalam Nawacita, khususnya Cita ketiga. Prioritas posisi Desa
tersebut membutuhkan komitmen pengawalan implementasi UU Desa
secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan untuk mencapai Desa
yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Salah satu wujud komitmen
tersebut ialah pengaturan tentang BUM Desa melalui Permendesa No.
4/2015 sebagai pelaksanaan amanat UU Desa.
BUM Desa dapat dimaknai sebagai:
1. Salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari
pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang
bersifat kolektif. Kemendesa PDTT mengembangkan konsep
Lumbung Ekonomi Rakyat. Dimana Lumbung Ekonomi Rakyat
adalah pengembangan ekonomi masyarakat Desa sesuai
potensi ekonomi desa baik atas prakarsa masyarakat Desa
dan/atau prakarsa Pemerintah Desa yang dilakukan dengan
mengutamakan kepentingan masyarakat Desa.
2. Salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia di Desa.
3. BUM Desa sebagai salah satu bentuk kemandirian ekonomi
Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis
bagi usaha ekonomi kolektif Desa.
18 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
B. BUM DESA Dan Tradisi Berdesa
Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental
yang mengiringi pendirian BUM Desa. Tradisi Berdesa sejajar dengan
kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap
daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa.
Inti gagasan dari Tradisi Berdesa dalam pendirian BUM Desa adalah:
1. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama,
solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan
usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan
lebih luas.
2. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui
praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk
pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh
BUM Desa.
3. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi
Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan
masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang
dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial
dan bisnis ekonomi.
4. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan
oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di
bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh
Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
5. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa
dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata
kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi
kolektif.
6. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program
yang diinisiasi oleh pemerintah (government driven; proyek
pemerintah) menjadi “milik Desa”.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 19
C. BUM DESA DAN ASAS UTAMA UU DESA: “REKOGNISI-
SUBSIDIARITAS”
Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa
PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Definisi Kewenangan
Lokal Berskala Desa dalam Pasal 1 angka 4 Permendesa PDTT No.
1/2015 tersebut adalah:
“Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan
oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan
prakarsa masyarakat Desa”.
Permendesa PDTT tersebut di atas merupakan pendasaran bagi
BUM Desa untuk dimasukkan sebagai salah satu bentuk kewenangan
lokal berskala Desa. Oleh karenanya, berkaitan dengan keberadaan-
faktual BUM Desa sebagai bagian dari Kewenangan Lokal Berskala
Desa, Kemendesa PDTT telah memasukkan pendirian dan pengelolaan
BUM Desa ke dalam Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang
pengembangan ekonomi lokal Desa (vide Pasal 12 huruf m Permendesa
PDTT No. 1/2015).
Adapun penetapan BUM Desa dikategorikan ke dalam Kewenangan
Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa (vide Pasal 8 huruf
l Permendesa PDTT No. 1/2015). Hal ini dimaksudkan agar pendirian,
penetapan dan pengelolaan BUM Desa didasarkan pada Asas
Rekognisi dan Asas Subsidiaritas.
Rekognisi dan Subsidiaritas terhadap BUM Desa (c.q. Permendesa
PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa), paralel dengan
(i) Permendesa PDTT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan (ii)
Permendesa PDTT No. 4 /2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa. Artinya, seluruh aspek BUM
Desa harus dibahas bersama dalam Musyawarah Desa sebagai “forum
tertinggi”.
20 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Dalam jalur teknokratik, pembentukan dan pengembangan BUM Desa
dimasukkan ke dalam RPJM Desa bidang pelaksanaan pembangunan
Desa, khususnya untuk rencana kegiatan pengembangan usaha
ekonomi produktif. Penyusunan RPJM Desa paralel dengan Perbup/
walikota dan Perdes tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
yang didalamnya terdapat pendirian, penetapan dan pengembangan
BUM Desa. Dengan demikian, BUM Desa dijalankan berdasar Asas
Rekognisi-Subsidiaritas dan sinkron dengan aspek teknokratik dalam
pembangunan Desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa).
1. MENGAWALI PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN
BUM DESA
A. Pembentukan Dan Pendirian BUM DESA
Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan
Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa [vide Pasal 87 ayat (1) UU
Desa, Pasal 132 ayat (1) PP No. 43/2014, dan Pasal 4 Permendesa
PDTT No. 4/2015]. Frasa “dapat mendirikan BUM Desa” dalam peraturan
perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan
dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha
ekonomi. Dari ketentuan tersebut, Pendirian BUM Desa didasarkan
atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:
a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
b) potensi usaha ekonomi Desa;
c) sumberdaya alam di Desa;
d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk
pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk
dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 21
Dalam aras sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan
legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa. Di dalam Peraturan Bupati tersebut dicantumkan
rumusan pasal (secara normatif) tentang:
a) pendirian dan pengelolaan BUM Desa ke dalam ketentuan
tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang
pengembangan ekonomi lokal Desa;
b) penetapan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan
Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa.
Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut
dengan memasukkan pendirian, penetapan, dan pengelolaan BUM
Desa.
Baik Peraturan Bupati/Walikota maupun Perdes tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa yang memuat BUM Desa tersebut harus sinkron dengan
isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan
BUM Desa dalam perencanaan bidang pelaksanaan pembangunan
Desa (item: rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif).
22 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Gambar
Alur Pendirian BUM Desa
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 23
B. Langkah Pelembagaan BUM Desa
Proses pelembagaan pelembagaaan BUM Desa harus dilakukan
secara partisipatif. Tujuannya agar pendirian BUM Desa benar-benar
seirama dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi
Desa. Langkah-langkah pelembagaan tersebut adalah sebagai berikut.
PERTAMA, sosialisasi tentang BUM Desa. Inisiatif sosialisasi
kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa,
BPD, PLD (Pendamping Lokal Desa) baik secara langsung maupun
bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan
di kecamatan, (ii) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang
berkedudukan di Kabupaten, dan (iii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM,
Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan).
Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan
kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian,
manfaat pendirian dan lain sebagainya. Keseluruhan Pendamping perlu
melakukan upaya inovatif-progresif untuk meyakinkan masyarakat
bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa.
Perumusan hasil sosialisasi yang memuat pembelajaran dari BUM
Desa dan kondisi internal-eksternal Desa dapat dibantu oleh para
Pendamping. Substansi sosialisasi selanjutnya menjadi rekomendasi
pada pelaksanaan Musyawarah Desa yang mengagendakan pendirian/
pembentukan BUM Desa. Rekomendasi dari sosialisasi dapat menjadi
masukan untuk:
• Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang
BUM Desa oleh BPD dan nantinya akan menjadi Pandangan
Resmi BPD terkait BUM Desa; dan
• Bahan Pembahasan tentang BUM Desa yang disiapkan oleh
Pemerintah Desa dan akan disampaikan oleh Kepala Desa
kepada BPD.
KEDUA, pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa
atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
24 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Desa
diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
Pendirian atau pembentukan BUM Desa merupakan hal yang
bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat
dielaborasi kaitannya dengan pendirian/ pembentukan BUM Desa
secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan
berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
Salah satu tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah
Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang
BUM Desa oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para
Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat
sederhana yakni:
a) menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui
pengelolaan usaha/bisnis.
b) mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan
masyarakat luar Desa.
c) merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan
rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis
usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT
dan LKM) maupun tidak berbadan hukum.
d) klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha
ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang
alternatif unit usaha BUM Desa dengan tipe pelayanan atau
bisnis sosial dan bisnis penyewaan. Kedua tipe unit usaha BUM
Desa ini relatif minim laba namun minim resiko kerugian bagi
BUM Desa.
e) organisasi pengelola BUM Desa termasuk dalam susunan
kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus).
Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam
Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif
dalam Perdes tentang Pendirian BUM Desa. Adapun susunan
nama pengurus BUM Desa dipilih langsung dalam Musyawarah
Desa agar pengurus/pengelola BUM Desa mendapat legitimasi
penuh dari warga Desa. Kesepakatan atas subjek/orang dalam
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 25
susunan kepengurusan BUM Desa selanjutnya ditetapkan dalam
Keputusan Kepala Desa. Susunan kepengurusan organisasi
pengelola BUM Desa terdiri dari Penasihat, Pelaksana
Operasional dan Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan
dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi
semangat kekeluargaan dan kegotongroyonan.
f) modal usaha BUM Desa. Modal awal BUM Desa bersumber
dari APB Desa. Modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal
Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
g) rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM
Desa (AD/ART) dibahas dalam Musyawarah Desa dan hasil
naskah AD/ART itu diputuskan oleh Kepala Desa sebagaimana
diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP No. 47/2015. AD/ART tersebut
dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat
Desa tetap mendasari substansi AD/ART.
h) pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang
dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUM
Desa.
KETIGA, penetapan Perdes tentang Pendirian BUM Desa
(Lampiran: AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkandari Perdes).
Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan
dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala
Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.
26 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
TRANSFORMASI BUM DESA
A. Pengembangan Kerjasama Ekonomi Antar Desa Menuju BUM
Desa Bersama
Pada prinsipnya, BUM Desa Bersama didirikan dalam rangka
kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa. Jalur
implementasinya adalah melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi
oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar-Desa) untuk mengagendakan
pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama di tingkat kecamatan atau
kawasan perdesaan.
Hasil kesepakatan dalam Musyawarah antar-Desa tentang
pengelolaan aset ekonomi antar desa, dijadikan pertimbangan dalam
penetapan BUM Desa Bersama melalui Peraturan Bersama Kepala
Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
B. Bank Kredit Desa sebagai Unit Usaha BUM Desa
Isu kebijakan saat ini juga berkembang dengan kewenangan OJK
(Otoritas Jasa Keuangan) terhadap eksistensi dan transformasi BKD
(Bank Kredit Desa) menjadi BUM Desa. BUM Desa merupakan institusi
Desa yang ditetapkan melalui Perdes.
Di lain pihak, BKD dengan status BPR hanya dapat didirikan dan
dimiliki oleh WNI, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya
WNI, Pemda, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. Dengan
demikian, Desa tidak secara eksplisit dapat menjadi pemegang saham
BKD dengan status BPR.
Salah satu opsi kebijakannya adalah BKD melakukan transformasi
transformasi BKD (Bank Kredit Desa) menjadi LKM (Lembaga
Keuangan Mikro) dan berkedudukan sebagai unit usaha BUM
Desa dengan kepemilikan BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen
sebagai pemegang saham mayoritas.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 27
PENUTUP
Kebijakan BUM Desa pasca terbitnya UU Desa, PP No. 43/2014,
PP No. 47/2015 dan Permendesa PDTT, menghadapi tantangan yang
kompleks. Produk kebijakan BUM Desa terdahulu mengalami proses
transformasi yang didasarkan Agenda Nawa Cita, Asas Rekognisi-
Subsidiaritas dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Pendirian BUM Desa dalam paradigma Desa Membangun
kini menghadapi tantangan berupa Musyawarah Desa sebagai
instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup
bermasyarakat dan bernegara di Desa). Proses pendirian/pembentukan
BUM Desa sedapat mungkin menghindari government driven yang
mudah membuat BUM Desa “layu sebelum berkembang”. Di lain pihak,
tantangan bagi BUM Desa saat ini adalah melakukan transformasi
agenda government driven itu ke dalam praksis Kewenangan Lokal
Berskala Desa baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan.
Salah satu agenda pendirian/ pembentukan BUM Desa Bersama pada
basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan
BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari
bentuk BPR menuju LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berpeluang
menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum.
Keseluruhan agenda kebijakan gerakan usaha ekonomi Desa ini
membutuhkan Tradisi Berdesa agar pelaksanaannya nanti di lapangan
tetap mengakui, menghormati, dan memulyakan Desa di Indonesia.
***
28 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Bagian Tiga
KERJA SAMA:
Mengembangkan Jaringan Sosial
Dan Kemitraan
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 29
PENGANTAR
Sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial (social being) adalah
saling tergantung dan saling membutuhkan. Sifat dasar ini juga berlaku
pada masyarakat. Setiap kesatuan masyarakat tidak dapat hidup
terisolir, ia selalu terhubung dan membutuhkan masyarakat lain. Sifat
dasar tersebut lebih nyata lagi di zaman mutkahir.
Dalam lingkup Desa dan masyarakat Desa, sifat saling membutuhkan
tersebut tampil dalam berbagai bentuk. Misal dalam perdagangan,
pertukaran tenaga atau lapangan kerja, konsumsi air di sebuah
Desa yang sumbernya terletak di Desa lain, gotong-royong, dan
lain sebagainya. Di banyak daerah, sifat saling membutuhkan antar
Desa dapat terjalin dan diperkuat oleh faktor kekerabatan atau adat
istiadat yang sama. Singkatnya, sifat saling membutuhkan dan sifat
saling terhubung antar masyarakat merupakan kenyataan dasar yang
menandai kehidupan masyarakat manusia, sejak dulu hingga sekarang.
Kenyataan tersebut menjadi salah satu latar belakang pengaturan
kerja sama Desa dalam UU No. 6/2014. Visi pengaturan tersebut adalah
bahwa Desa harus mengembangkan sifat saling membutuhkan dan
keterhubungan di atas menjadi kerja sama (cooperation atau kooperasi)
yang berpijak pada aturan legal-konstitusional agar Desa mampu
mewujudkan kesejahteraan warganya sekaligus menjadi basis sosio-
budaya dan ekonomi nasional yang kokoh. Sifat saling membutuhkan
dan saling terhubung hanya akan melahirkan nilai lebih bila ditingkatkan
menjadi kerja sama.
Jaringan sosial (social network) dapat diibaratkan sebagai rantai
hubungan antar individu atau kelompok yang membentuk sebuah pola
tertentu. Pada dasarnya jaringan sosial ini terbangun melalui hubungan-
hubungan sosial yang bersifat sehari-hari, baik formal maupun informal.
Pada tingkat tertentu, hubungan-hubungan itu membentuk berbagai
macam rantai pengelompokkan seperti ekonomi, politik, tradisi,
kepercayaan/agama. Pemahaman atas pola jaringan sosial di Desa ini
penting bagi Pendamping Desa setidaknya karena empat alasan.
30 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Pertama untuk mengetahui pola-pola interaksi sosial, politik, dan
ekonomi yang ada di Desa sekaligus yang menghubungkan satu Desa
dengan Desa lain.
Kedua untuk memudahkan Pendamping dalam mendorong
terlaksananya kerja sama antar-Desa maupun dengan pihak ketiga
ketika dibutuhkan.
Ketiga untuk membantu mengatasi persoalan yang dihadapi
masyarakat desa, berdasar atas kekuatan sosial-budaya dan potensi
ekonomi yang dimiliki masyarakat Desa itu sendiri. Persoalan tersebut
seperti terbatasnya peluang kerja, struktur sumber daya ekonomi yang
kurang beragam, keterbatasan pendidikan, keterampilan, peralatan dan
modal. Sejumlah keterbatasan-keterbataan tersebut di atas sejatinya
dapat diatasi dengan pemanfaatan jaringan sosial yang terkembang
menjadi kerja sama.
Keempat, untuk mengantisipasi keterlibatan pihak di luar institusi
Desa dalam membangun Desa. Kerja sama dengan Pihak Ketiga,
seperti diatur dalam UU Desa, membutuhkan pengorganisasian yang
tepat atas jaringan sosial yang sudah ada agar kerja sama tersebut
tidak merugikan masyarakat Desa. Peran Pendamping Desa dalam
memfasilitasi proses kerjasama antar Desa atau dengan pihak ketiga
sangat vital agar kerjasama tersebut didasari pada tujuan memandirikan
desa.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 31
1. DASAR BERPIKIR DALAM MENGEMBANGKAN
JARINGAN DAN KERJASAMA
A. Kerja Sama Desa: Amanat UU Desa
Kerja sama diatur di Pasal 91-93 UU Desa. Ketentuan Pasal 1
mengatur bahwa “Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa
lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga”. Ketentuan tersebut
menginformasikan bahwa sifat kerja sama sesungguhnya opsional,
atau pilihan. Pengertiannya, sejauh kerja sama tersebut dibutuhkan
maka kerja sama dapat dilakukan, baik dengan Desa lain maupun
dengan pihak ketiga.
Sebagaimana ketentuan di Pasal 92 ayat (1), kerja sama antar-Desa
meliputi beberapa bidang:
a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk
mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
b. Kegiatan kemasyarakatn, pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat antar-Desa;
c. Bidang keamanan dan ketertiban.
Dilihat dari sudut pandang normatif, kerja sama Desa dilindungi dan
menjadi jalan keluar dari permasalahan keterbatasan sumber daya
Desa yang ditawarkan oleh UU Desa.
Dengan kewenangannya, Desa memiliki kesempatan yang sangat
luas untuk meletakkan penyelenggaraan kerja sama dalam tata nilai
sosio-kultural dan kebiasaan masyarakat Desa. Tujuan adaptasi sesuai
kewenangan lokal tersebut adalah agar kerja sama dilakukan atas dasar
konstruksi tata kultural yang ada di masyarakat. Sehingga kerja sama
dengan pihak lain (baik Desa lain maupun Pihak Ketiga) sinambung
baik dengan kebutuhan yang perlu dikerjasamakan sekaligus dengan
tata kultural masyarakat Desa itu sendiri.
UU Desa mengatur bahwa kerja sama harus dilakukan dengan
32 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
seutuhnya melibatkan partisipasi masyarakat atau warga Desa.
Sebab itu kerja sama terlebih dahulu harus disepakati di dalam Desa
melalui musyawarah Desa, sebelum dibicarakan dan disepakati
dalam musyawarah antar-Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerja
Sama Antar Desa. Kerja sama antar-Desa juga harus memiliki pijakan
legalnya, yakni melalui Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa dan
Peraturan Bersama Kepala Desa.
Mekanisme yang sama (musyawarah Desa) juga harus dilalui
dalam penyelenggaraan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga. Dalam
hubungannya dengan Pihak Ketiga, pelaksanaan kerja sama diatur
dengan Perjanjian Bersama (Pasal 143 ayat (3) PP No. 43/2014).
Isi Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama,
menurut ketentuan Pasal 143 ayat (4) PP No. 43/2014, setidaknya
memuat:
a. Ruang lingkup kerja sama
b. Bidang kerja sama
c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama
d. Jangka waktu
e. Hak dan kewajiban
f. Pendanaan
g. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, dan
h. Penyelesaian perselisihan.
Pijakan legal konstitusional di atas harus difahami Pendamping dan
oleh Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa). Bagi Pendamping
Desa, pemahaman tersebut mutlak karena perannya sebagai tempat
bertanya masyarakat Desa dan penggerak partisipasi masyarakat
Desa.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 33
B. Dasar Pengembangan Jaringan Dan Kerja Sama Desa
Mengapa kerja sama penting dilakukan? Dan mengapa sebaiknya
kerja sama dikembangkan dari pola jaringan sosial yang sudah ada?
Dua pertanyaan tersebut setidaknya yang harus dijawab di bagian ini.
Pertama dan yang paling mendasar adalah fakta bahwa potensi alam,
sumber daya manusia, dan modal sosial Desa tidak selalu sama antara
satu Desa dengan Desa yang lain. Pada saat yang sama hubungan
masyarakat antar beberapa Desa tersebut bisa telah terjalin dengan
baik, atau sebaliknya, terdapat gejala-gejala perselisihan atau konflik.
Sebagai ilustrasi, yang kami singgung di bab sebelumnya, sebuah
sungai yang melintasi beberapa Desa dan digunakan untuk berbagai
keperluan seperti irigasi, mandi-cuci-kakus, atau bahkan untuk
konsumsi. Apabila di bagian hulu sungai itu dimanfaatkan untuk irigasi
atau untuk mencuci, bagian aliran yang lebih rendah akan mendapatkan
air yang kotor. Padahal masyarakat di situ membutuhkan air tersebut
untuk keperluan konsumsi. Hubungan antara masyarakat Desa di dua
Desa (atau lebih) tersebut dapat digunakan sebagai titik mula untuk
membangun kerja sama.
Kedua, Desa-Desa kedepan sudah harus mampu menciptakan
kemandirian khususnya dalam sistem pemenuhan kebutuhan dasar
seperti pangan, energi, pendidikan dan kesehatan. Desa tidak dituntut
untuk memenuhi secara mandiri kebutuhan energi apabila di Desa
tersebut tidak ada potensi energi. Maksud dari sistem pemenuhan
kebutuhan daar adalah cara atau mekanisme yang yang dikembangkan
oleh kebiasaan dan jaringan sosial yang telah terbangun di Desa untuk
memenuhi kebutuhan itu, yaitu melalui kerja sama atau kemitraan. Di
sinilah makna sifat saling membutuhkan antar masyarakat.
Ketiga, tuntutan pengelolaan sumber daya alam semakin diarahkan
pada penyesuaian tata kelola dengan prinsip-prinsip keberlanjutan
(sustainability). Sebab itu kerja sama, kemitraan, dan pengembangan
potensi jaringan sosial ditekankan pada beberap aspek, meliputi:
34 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
1. Keberlanjutan ekologi, dimana pemanfaatan sumber daya
alam dilakukan dengan tidak merusak lingkungan dan
senangtiasa memperhatikan daya dukung ekologinya.
2. Keberlanjutan sosial ekonomi yang mengacu pada
kesejahteraan masyarakat pedesaan.
3. Keberlanjutan komunitas masyarakat pedesaan yang
mengacu pada terjaminnya peran masyarakat dalam
pembangunan, dan jaminan akses komunitas pada sumber
daya alam,
4. Keberlanjutan institusi yakni yang mencakup institusi politik,
institusi sosial-ekonomi dan institusi pengelola sumber daya.
Keempat, program-program pembangunan seringkali menciptakan
ketergantungan masyarakat Desa atau Desa pada penyelenggara
program. Kerja sama dan jaringan sosial dimaksudkan untuk
memperkuat kapasitas masyarakat lintas Desa dalam memperkuat
kemandirannya sebagai subjek pembangunan. Melalui kerja sama,
posisi Desa (dalam hal ini Pemerintah Desa dan masyarakat Desa)
dituntut untuk memikirkan secara serius kebutuhan dan kepentingannya
untuk dibicarakan atau dinegosiasikan dengan Desa lain.
Dasar pemikiran selanjutnya terkait dengan keberadaan Pendamping
Desa yang dimulai tahun 2015 ini. Keberadaan Pendamping Desa
adalah untuk melanjutkan dan meningkatkan visi kerja program PPK
(Program Pengembangan Kecamatan, 1998-2008) dan PNPM MPd
(2009-2014). Perbedaan mendasar dalam program Pendampingan
Desa adalah prinsip partisipatif dan keaktoran masyarakat Desa dalam
penyelenggaraan program pembangunan Desa seperti digariskan oleh
UU No. 6/2014 tentang Desa. Pendamping dituntut untuk memahami
secara komprehensif karakteristik sosial-budaya, sosial-politik, dan
sosial-ekonomi masyarakat Desa yang ia dampingi. Dalam konteks
kerja sama Desa, prinsip tersebut juga harus diperhatikan.
Sebab itu, kelima, jaringan sosial harus diketahui dan dikenal
betul untuk menjahit seluruh kekuatan ekonomi dan politik di wilayah
perdesaan agar secara keseluruhan, masyarakat Desa dapat terlibat
dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Aktor atau subjek-
subjek dalam jaringan sosial pada dasarnya merupakan mitra strategis
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 35
desa yang harus senantiasa dijaga dan dikembangkan untuk memajukan
pembangunan di desa.
2. PRINSIP & LANGKAH PENGEMBANGAN
JARINGAN SOSIAL DAN KERJASAMA
A. Prinsip Pengembangan Jaringan Sosial Dan Kerja Sama
Tugas Pendamping setelah memahami jaringan sosial adalah
mengembangkannya sebagai modal bagi kerja sama dan Pembangunan
Desa. Dalam pengembangan tersebut, prinsip-prinsip berikut ini harus
diperhatikan oleh Pendamping:
• Pendamping harus meyakini, mengakui dan menghargai bahwa
setiap individu atau lembaga memiliki potensi yang merupakan
modal dasar dalam mewujudkan visi pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.
• Modal dasar tersebut perlu dikembangkan dan ditingkatkan
mutunya, serta dipadukan lewat proses dialog dan musyawarah
dalam wadah jaringan.
• Musyawarah dan dialog adalah roh dari pendampingan desa.
• Pendamping desa harus senangtiasa menciptakan peluang
dengan mengembangkan sistem dan mekanisme, agar
potensi jaringan sosial yang terbentuk senantiasa diperhatikan
dan dipertimbangkan dalam proses pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.
B. Langkah Pengambangan Jaringan Sosial
Langkah-langkah pengembangan jaringan sosial dimulai dari
identifikasi jaringan sosial itu sendiri. Secara keseluruhan langkah-
langkah tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama. Membantu aparat pemerintahan desa dalam
36 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
mengidentifikasi kelompok-kelompok sosial dan potensi perannya
masing-masing dalam proses pembangunan dan pemberdayaan desa.
Kedua. Melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok sosial
di perdesaan dengan membangun dialog yang baik. Dialog dilakukan
dalam rangka memahami realitas pedesaan untuk merangsang
kehendak kerja sama masayarakat Desa setempat. Dialog dilakukan
sebaik mungkin dengan prinsip sikap dasar:
a. Menghargai hak-hak dari lawan komunikasi, bukan saling
meniadakan.
b. Memiliki kepekaan terhadap realitas yang dihadapi
oleh masyarakat Desa untuk membantu Pendamping
menemukan potensi dasar dari kelompok sosial tersebut.
c. Kerendahan hati, yaitu kemauan yang tinggi untuk belajar
dari orang lain dan menyampaikan pandangan tanpa sikap
menggurui.
d. Membangun kepercayaan bahwa manusia pada dasarnya
diciptakan sebagai subjek. Karena itu manusia mempunyai
tanggungjawab mengelola alam semesta untuk mewujudkan
kesejahteraan.
e. Rasa empati terhadap sesamanya dan alam semesta untuk
membangun rasa percaya diri lawan dialog.
f. Bersedia mendengarkan orang lain dan memahami diri
sendiri, untuk menumbuhkan optimisme lawan dialog.
Ketiga. Mengajak dan melibatkan kelompok-kelompok sosial
dalam pertemuan yang diinisiasi oleh desa. Pertemuan ini menjadi
ruang bagi setiap kelompok sosial untuk berbagi pengalaman dan
pemikiran terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan desa
dalam suatu dialog yang bebas. Bahkan jika diperlukan suatu
musyawarah memungkinkan menumbuhkan satu jaringan kerja.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 37
Keempat. Menyusun rencana kerja dan program bersama yang
didasarkan atas kemampuan dan potensi masing-masing kelompok
sosial.
Kelima. Melakukan diskusi aksi-refleksi. Diskusi aksi-refleksi
ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dan sinergisitas dari
jaringan sosial yang terbentuk.
C. Langkah Identifikasi Kebutuhan Kerja Sama
Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pendamping desa dalam
mengembangkan kerjasama, antara lain :
Pertama. Pendamping desa membantu Pemerintah Desa dalam
mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
di desa. Analisis terhadap potensi ini menjadi modal dasar dalam
membangun kerjasama dengan pihak luar desa.
Kedua. Pendamping desa bersama-sama dengan pemerintah
desa mengidentifikasi kebutuhan kerja sama sekaligus
mengidentifikasi Desa lain atau Pihak Ketiga yang mungkin menjadi
mitra kerja sama.
Ketiga. Pendamping desa bersama-sama dengan pemerintah
Desa menganalisis dan menentukan jenis-jenis kegiatan dan
program-program yang perlu dikerjasamakan dengan pihak luar
dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
peningkatan rasa aman warga desa.
Keempat. Pendamping desa mendorong penyelenggaraan
musyawarah Desa untuk membicarakan perlunya kerja sama,
sesuai dengan mekanisme yang berlaku mengenai musyawarah
Desa menurut Permendesa PDT Transmigrasi No. 2/2015.
Langkah-langkah di atas, baik dalam pengembangan jaringan
sosial maupun kerja sama tidak bersifat mutlak dan dapat
dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat Desa setempat.
38 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
PENUTUP
Wawasan umum dalam empat bagian yang diuraikan dalam tulisan
ini harus dilengkapi dengan pengetahuan mekanisme legal yang
dibicarakan dalam seri bacaan sebelumnya. Dalam hal ini, Pendamping
Desa harus faham betul mengenai mekanisme permusyawaratan Desa
serta tata aturan penetapan Peraturan Desa, Peraturan Bersama
Kepala Desa.
Di luar langkah-langkah yang telah digambarkan di bagian (4) di atas,
penyesuaian diri dan daya serap Penamping atas situasi lingkungan
Desa tempat ia bertugas sangat menentukan. Dalam hubungannya
dengan jaringan sosial dan kerja sama, daya serap dan kejelian serta
sensitifitas Pendamping dalam memetakan jaringan sosial sangat
penting untuk dikembangkan[.]
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 39
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia
40 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Anda mungkin juga menyukai
- Panduan Doa Novena Tiga Salam MariaDokumen3 halamanPanduan Doa Novena Tiga Salam Marianatalia100% (3)
- PRAKTIKUM GenetikaDokumen14 halamanPRAKTIKUM GenetikanataliaBelum ada peringkat
- Tugas Asisten LaboratoriumDokumen4 halamanTugas Asisten LaboratoriumnataliaBelum ada peringkat
- Kleistogami Adalah Penyerbukan Sendiri Yang Berlangsung Pada Satu Bunga Sewaktu Bunga Masih Belum MekarDokumen1 halamanKleistogami Adalah Penyerbukan Sendiri Yang Berlangsung Pada Satu Bunga Sewaktu Bunga Masih Belum MekarnataliaBelum ada peringkat
- Panduan Doa Novena Tiga Salam MariaDokumen3 halamanPanduan Doa Novena Tiga Salam MarianataliaBelum ada peringkat
- Ciri Ciri Makhluk Hidup PPT KuliahDokumen8 halamanCiri Ciri Makhluk Hidup PPT KuliahnataliaBelum ada peringkat
- Contoh SK PKKDokumen3 halamanContoh SK PKKnatalia100% (5)
- L6 - Surat Keterangan Kepala DesaDokumen1 halamanL6 - Surat Keterangan Kepala DesanataliaBelum ada peringkat
- LaboratoriumDokumen4 halamanLaboratoriumnataliaBelum ada peringkat
- Reproduksi TumbuhanDokumen36 halamanReproduksi TumbuhannataliaBelum ada peringkat
- Buku InventarisDokumen2 halamanBuku InventarisNathalia LaseBelum ada peringkat
- Reproduksi HewanDokumen43 halamanReproduksi HewannataliaBelum ada peringkat
- Contoh SK PKKDokumen3 halamanContoh SK PKKnatalia100% (5)
- Arti LambangDokumen2 halamanArti LambangnataliaBelum ada peringkat