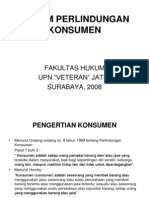Keterkaitan Antara Birokrasi Dengan Politik Telah Berlangsung Sejak Awal Abad 20
Diunggah oleh
star-manHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Keterkaitan Antara Birokrasi Dengan Politik Telah Berlangsung Sejak Awal Abad 20
Diunggah oleh
star-manHak Cipta:
Format Tersedia
A. Latar Belakang Keterkaitan antara birokrasi dengan politik telah berlangsung sejak awal abad 20an.
Pemikiran yang lebih dominan pada periode 1900-1927 lebih mengarah kepada dikotomi politik dengan administrasi negara. Pelopor dari pemikiran-pemikiran itu di antaranya adalah Frank Goodnow, Leonard White dan Wodrow Wilson, Leonard White bahkan secara tegas menyatakan, politik seharusnya tidak boleh ikut campur tangan dalam proses administrasi negara (Ali Mufiz: 1986). Mereka berusaha membedakan fungsi politik dengan fungsi administrasi negara. Fungsi politik, adalah pembuatan policy (kebijakan) atau ekspresi dari kemauan negara, sedangkan fungsi administrasi negara adalah pelaksanaan policy tersebut. Baru pada tahun 1980-an, upaya untuk mengaitkan politik dengan administrasi mulai menguat. Sampai sekarang pun, ternyata perbincangan itu belum selesai. Dalam konteks Indonesia, pembicaraan seputar politisasi birokrasi masih sangat menarik, terutama karena praktek penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia masih sangat kental dengan nuansa politik. Praktek paling vulgar terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, birokrasi diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk memobilisasi massa dengan didesakkannya monoloyalitas kepada pegawai negeri (birokrat). Bahkan birokrasi pada masa Orde Baru dianggap sebagai salah satu soko guru kekuasaan Soeharto bersamasama dengan ABRI dan Golkar. Dalam setiap pemilihan umum, pegawai negeri dan keluarganya tidak sekadar diharuskan untuk memilih Golkar, melainkan juga diharuskan
untuk menggalang dukungan dari masyarakat di wilayahnya masing-masing. Cara ini memang sangat efektif untuk menjaga kelanggengan kekuasaan Orde Baru. Di akhir kekuasaan Orde Baru, politisasi birokrasi dikritik habis-habisan oleh gerakan proreformasi. Birokrasi berusaha untuk dikembalikan pada fungsi dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Ide ini sejalan dengan pemikiran sarjana-sarjana administrasi Barat yang berusaha melakukan reinventing government pada awal 1990-an. Salah satu gagasan penting dalam reinventing government adalah bagaimana agar public service menjadi orientasi utama dari birokrasi pemerintahan. Upaya untuk menghentikan terjadinya politisasi birokrasi itu ternyata tidak mudah. Dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah di era reformasi ini, politisasi birokrasi tidak hanya tetap terjadi, tetapi juga muncul politisasi birokrasi dengan varian yang baru. Kalau politisasi birokrasi di era Orde Baru terjadi secara sentralized dalam skala nasional di bawah kendali langsung Presiden Soeharto, di era otonomi daerah ini fokus politisasi birokrasi bergeser di kabupaten/ kota. Sedangkan pengendali dari politisasi birokrasi di era otonomi daerah adalah bupati atau walikota di daerahnya masing-masing, sehingga partai politik yang mendapatkan keuntungan dari praktek politisasi birokrasi ini juga beragam, tergantung dari latar belakang politik bupati/ wali kota. Tetapi satu hal yang harus dicatat adalah bahwa politisasi birokrasi tidak terjadi di semua pemerintah kabupaten /kota. Hal ini berarti bahwa terjadinya politisasi birokrasi tergantung pada good will dari bupati/wali kota di daerahnya masing-masing. Perangkat pemerintahan di tingkat pusat tidak lagi mampu melakukan penetrasi terhadap pegawai
negeri di tingkat kabupaten/ kota, karena kewenangan untuk mengelola pegawai negeri sipil sudah dilimpahkan kepada bupati/ wali kota. Bupati /wali kota mampu menjadi pengendali dari politisasi birokrasi karena di era otonomi daerah ini bupati /wali kota mempunyai seperangkat kewenangan yang dapat membuat pegawai negeri sipil mau tidak mau harus tunduk kepada bupati/ wali kota, kecuali bersedia menanggung risiko terhambat kariernya di birokrasi. Kewenangan itu antara lain dalam hal penentuan pejabat eselon, kewenangan bupati/wali kota dalam membuat SK pengangkatan PNS dan kewenangan dalam membuat SK kenaikan pangkat bagi PNS. Dalam hal kewenangan ini terdapat permasalah pengangkatan PNS juga mendapat suatu perhatian penting dikarenakan seorang kepala daerah mepunyai kepentingan tertentu terhadap pegawai, dimana seorang pegawai juga seorang masyarakat yang mempunyai hak suara Tetapi bukankah di era reformasi ini telah terjadi pergeseran kekuasaan dari tangan eksekutif ke tangan legislatif yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya legislatif heavy? Di mana peran lembaga legislatif di kabupaten/ kota terhadap terjadinya politisasi birokrasi? Memang kalau melihat kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif, seharusnya politisasi birokrasi hanya terjadi pada kabupaten/ kota yang dikuasai secara mayoritas (lebih dari 50 %) oleh salah satu partai dan bupati / waliko tanya berasal dari partai mayoritas tersebut. Karena kalau kondisinya semacam itu, kepentingan politik antara
eksekutif dengan legislatif akan sejalan sehingga lembaga legislatif akan selalu mendukung langkah-langkah politik yang dilakukan oleh bupati/ wali kota yang menguntungkan partai pemegang suara mayoritas. Sedangkan kalau bupati/ wali kota tidak didukung oleh suara mayoritas di DPRD, maka akan sangat mudah digoyang oleh legislatif, bahkan tidak mustahil terjadi upaya pelengseran bupati oleh DPRD. Kalau kondisinya seperti ini, tentunya bupati/ wali kota tidak akan berani melakukan politisasi birokrasi untuk kepentingan partainya, karena akan menjadi musuh bersama seluruh partai politik di daerah tersebut. Tetapi ternyata yang terjadi tidak demikian, dalam era otonomi daerah, pada euforia legislative heavy ini, lembaga legislatif tetap tidak mampu menghentikan terjadinya mobilisasi aparatur pemerintah daerah untuk mendukung salah satu partai tertentu. Di Jawa Tengah misalnya, tidak ada partai politik yang menguasai legislatif secara mayoritas di 35 kabupaten/ kota, tetapi politisasi birokrasi tetap terjadi. Faktor yang paling mungkin menjadi penyebab dari terjadinya politisasi birokrasi secara leluasa oleh bupati/wali kota tanpa adanya perlawanan dari lembaga legislatif yang partainya dirugikan adalah karena anggota Dewan tersebut telah membuat kesepakatankesepakatan yang saling menguntungkan dengan bupati/ wali kota di daerah tersebut. Dari deal itu, tentunya anggota Dewan tersebut akan mendapatkan kompensasi material yang tidak sedikit. Kompensasi material itu yang dapat membuat seorang anggota Dewan tidak merasa dirugikan oleh terjadinya politisasi birokrasi, karena memang yang dirugikan hanya partainya.
Kalau begini, berarti anggota DPRD kabupaten/ kota tidak dapat diharapkan untuk menghentikan terjadinya politisasi birokrasi. Pihak yang seharusnya berperan aktif setelah wakil partai yang duduk di lembaga legislatif tidak dapat diharapkan, tentunya adalah pimpinan partai politik di level yang lebih tinggi (baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat pusat). Institusi partai di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat ini dapat berperan dalam menghentikan terjadinya politisasi birokrasi dengan memberikan sanksi secara tegas kepada anggota legislatif dari partai tersebut yang terbukti membiarkan terjadinya politisasi birokrasi di daerah tersebut. Terlebih kepada wakil rakyat dari partai itu yang terbukti mendapatkan kompensasi material dari bupati/wali kota. Partai harus tegas, tidak saja karena perilaku anggota Dewan tersebut merugikan partai, tetapi lebih dari itu, perilaku anggota Dewan yang membiarkan terjadinya politisasi birokrasi dengan menerima kompensasi material memperlihatkan anggota Dewan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan partai. Perilaku semacam ini tidak boleh dibiarkan. Sudah seharusnya anggota DPRD kabupaten/ kota yang terbukti membiarkan terjadinya politisasi birokrasi di -recall dan diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan partai. Dengan ancaman sanksi tegas semacam ini tentunya akan membuat anggota Dewan dan suatu partai tidak berani "main mata" dengan bupati/ wali kota. Di tengah berbagai hambatan prosedural yang secara tidak langsung menjadi pelindung bupati/ wali kota dalam melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan, terobosan ini merupakan satu-satunya cara yang paling mungkin dilakukan untuk menggugah kemauan
dan meningkatkan nyali anggota Dewan dalam mengingatkan bupati/ wali kota sehingga peluang terjadinya politisasi birokrasi dapat diminimalisir. Partai politik tidak perlu merasa kesulitan dalam menghadirkan bukti ataupun saksi. Pimpinan partai dapat menggunakan informasi dari masyarakat, media, kader partai atau dari mana pun sebagai dasar untuk memanggil dan meminta keterangan lebih lanjut kepada anggota DPRD kabupaten/ kota. Hal ini tidak sulit karena indikasi dan praktek terjadinya politisasi birokrasi sangat mudah dilihat karena selalu melibatkan banyak orang dan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat
Anda mungkin juga menyukai
- KodeKlasifikasiDokumen23 halamanKodeKlasifikasistar-manBelum ada peringkat
- Lampiran 1 - Format Daftar Riwayat Hidup - 608Dokumen9 halamanLampiran 1 - Format Daftar Riwayat Hidup - 608romansacute33% (3)
- Administrasi Negara Dan PublikDokumen27 halamanAdministrasi Negara Dan Publikstar-manBelum ada peringkat
- LehDokumen7 halamanLehstar-manBelum ada peringkat
- Tugas Makalah Politik HukumDokumen10 halamanTugas Makalah Politik Hukumstar-manBelum ada peringkat
- Materi Hukum Perlindungan Konsumen-WiwinDokumen10 halamanMateri Hukum Perlindungan Konsumen-Wiwinpaijo18Belum ada peringkat