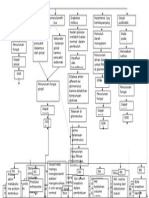Pendahuluan
Pendahuluan
Diunggah oleh
Annisa Wahyuningsih0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
17 tayangan23 halamanJudul Asli
Pendahuluan.docx
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
17 tayangan23 halamanPendahuluan
Pendahuluan
Diunggah oleh
Annisa WahyuningsihHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 23
ILMU DASAR KEPERAWATAN
FISIOLOGI SISTEM MUSKULOSKELETAL
( MAKALAH INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH ILMU DASAR KEPERAWATAN )
DISUSUN OLEH :
Kelompok 3
Achmad Suhaili
Annisa Wahyuningsih
Erfan Efendi
Kholifatul Jannah
Nur hanifah
Shulton
Yeni Gres Tannewa
JURUSAN S1 KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SURABAYA
2013
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada tubuh orang sakit kita harus terlebih
dahulu mengetahui struktur dan fungsi tiap alat dari susunan tubuh manusia yang sehat dalam
kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia merupakan
dasar yang penting dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Dengan mengetahui struktur
dan fungsi tubuh manusia, seorang perawatan professional dapat makin jelas manafsirkan
perubahan yang terdapat pada alat tubuh tersebut.
1.2 Tujuan
1.2.1 Tujuan Umum
Untuk memperoleh pengetahuan tentang fisiologi sistem mukuloskeletal.
1.2.2 Tujuan Khusus
a. Mengetahui fisiologi sistem muskuloskeletal
b. Dapat menjadikan suatu acuan dalam keperawatan
1.3 Manfaat
1. Dapat menambah ilmu
2. Mengetahui fisiologi pada sistem muskuloskeletal
3. Sebagai suatu acuan pembelajaran mahasiswa keperawatan
BAB II
TINJAUAN TEORI
Fisiologi berasal dari kata Fisis (physis): alam atau cara kerja. Logos (logi): ilmu
pengetahuan. Dari kata tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian fisiologi adalah
ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana alat tubuh itu bekerja. Fisiologi
adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian
dari alat-alat tubuh dan sebagainya.
Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan mengukur
pergerakan. Sistem muskuloskeletal merupakan suatu system yang dibentuk oleh tulang,
sendi dan otot. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo: otot dan skeletal: tulang. Muskulo
atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh ( ilmu = Myologi ). Skeletal atau osteo adalah
tulang kerangka tubuh (ilmu = Osteologi). Muskuloskeletal disebut juga Lokomotor.
Tulang manusia saling berhubungan satu dengan yang lain dalam berbagai bentuk
untuk memperoleh fungsi system muskuloskeletal yang optimum. Aktivitas gerak tubuh
manusia tergantung pada efektifnya interaksi antara sendi yang normal unit-unit
neuromuskular yang menggerakkannya. Elemen-elemen tersebut juga berinteraksi untuk
mendistribusikan stress mekanik ke jaringan sekitar sendi. Otot, ligamen, rawan sendi dan
tulang saling bekerjasama di bawah kendali sistem saraf agar fungsi tersebut dapat
berlangsung dengan sempurna.
Tulang atau rangka adalah penopang tubuh manusia. Tanpa tulang, pasti tubuh kita
tidak bisa tegak berdiri. Tulang mulai terbentuk sejak bayi dalam kandungan, berlangsung
terus sampai dekade kedua dalam susunan yang teratur. Mengapa kita bisa bergerak?
Manusia bisa bergerak karena ada rangka dan otot. Rangka tersebut tidak dapat bergerak
sendiri, melainkan dibantu oleh otot. Dengan adanya kerja sama antara rangka dan otot,
manusia dapat melompat, berjalan, bergoyang, berlari, dan sebagainya.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Fisiologi Sistem Tulang
3.1.1 Fungsi Tulang
a. Fungsi umum tulang
Secara umum, fungsi tulang adalah sebagai berikut:
1. Formasi kerangka
Tulang-tulang membentuk rangka tubuh untuk menentukan ukuran tulang dan menyokong
struktur tubuh yang lain.
2. Formasi sendi-sendi
Tulang-tulang membentuk persendian yang bergerak dan tidak bergerak tergantung dari
kebutuhan fungsional. Sendi yang bergerak menghasilkan bermacam-macam pergerakan.
3. Perlekatan otot
Tulang-tulang menyediakan permukaan untuk tempat melekatnya otot, tendon, dan
ligamentum. Untuk melaksanakan pekerjaan yang layak dibutuhkan suatu tempat melekat
yang kuat dan untuk itu disediakan oleh tulang.
4. Sebagai pengungkit
Untuk bermacam-macam aktivitas selama pergerakkan.
5. Penyokong berat badan
Memelihara sikap tegak tubuh manusia dan menahan gaya tarikan dan gaya tekanan yang
terjadi pada tulang sehingga dapat menjadi kaku dan lentur.
6. Proteksi
Tulang membentuk rongga yang mengandung dan melindungi struktur-struktur yang halus
seperti otak, medulla spinalis, jantung, paru-paru, alat-alat dalam perut, dan panggul.
7. Haemopoiesis
Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah, tetapi terjadinya
pembentukan sel-sel darah sebagian besar terjadi di sumsum tulang merah.
8. Fungsi immunologi
Limfosit B dan makrofag-makrofag dibentuk dalam system retikuloendotelial sumsum
tulang. Limfoist B diubah menjadi sel-sel plasma yang membentuk antibody guna keperluan
kekebalan kimiawi, sedangkan makrofag merupakan fagositotik.
9. Penyimpanan kalsium
Tulang mengandung 97% kalsium tubuh, baik dalam bentuk anorganik maupun dalam
bentuk garam-garam, terutama kalsium fosfat. Sebagian besar fosfor disimpan dalam tulang
dan kalsium dilepas dalam darah bila dibutuhkan.
b. Fungsi khusus tulang
Secara khusus tulang mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Sinus-sinus paranasalis dapat menimbulkan nada khusus pada suara.
2. Email gigi dikhususkan untuk memotong, menggigit, dan menggilas makanan. Email
merupakan struktur yang terkuat dari tubuh manusia.
3. Tulang-tulang kecil telinga berfungsi sebagai pendengaran dalam mengonduksi
gelombang suara.
4. Panggul wanita dikhususkan untuk memudahkan proses kelahiran bayi.
3.1.2 Proses Pertumbuhan Tulang
Rangka manusia terbentuk pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pada waktu
perkembangan embrio. Tulang yang terbentuk mula-mula adalah tulang rawan (kartilago)
yang berasal dari jaringan mesenkim (jaringan embrional). Sesudah kartilago terbentuk,
rongga yang ada di dalamnya akan terisi oleh osteoblas.
Sel-sel osteoblas terbentuk secara konsentris yaitu dari dalam keluar. Setiap sel
melingkari pembuluh darah dan serabut saraf yang membentuk sistem Havers. Substansi di
sekitar tulang disebut matriks tulang, tersusun atas senyawa protein. Selanjutnya terjadi
pengisian kapur dan fosfor sehingga matriks tulang menjadi keras. Pengerasan tulang disebut
osifikasi.
Osifikasi dibedakan menjadi 2 macam sebagai berikut.
a. Osifikasi kondral yaitu pembentukan tulang dari tulang rawan. Terjadi pada tulang pipa
dan tulang pendek.
b. Osifikasi desmal yaitu pembentukan tulang dari membran jaringan mesenkim. Terjadi pada
tulang pipih.
Pertumbuhan Tulang
Proses pertumbuhan tulang manusia dimulai sejak janin berusia delapan minggu
sampai umur kurang lebih 25 tahun, bahkan lebih dari itu masih terjadi pembentukan tulang.
Urutan proses pembentukan tulang (osifikasi) sebagai berikut.
a. Tulang rawan pada embrio mengandung banyak osteoblas, terutama pada bagian tengah
epifisis dan bagian tengah diafisis, serta pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan.
b. Osteosit terbentuk dari osteoblas, tersusun melingkar membentuk sistem Havers. Di tengah
sistem Havers terdapat saluran Havers yang banyak mengandung pembuluh darah dan
serabut saraf.
c. Osteosit mensekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Setelah mendapat
tambahan senyawa kalsium dan fosfat tulang akan mengeras.
d. Selama terjadi penulangan, bagian epifisis dan diafisis membentuk daerah antara yang
tidak mengalami pengerasan, disebut cakraepifisis. Bagian ini berupa tulang rawan yang
mengandung banyak osteoblas.
e. Bagian cakraepifisis terus mengalami penulangan. Penulangan bagian ini menyebabkan
tulang memanjang.
f. Di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoblas yang merusak tulang sehingga tulang
menjadi berongga kemudian rongga tersebut terisi oleh sumsum tulang.
Perkembangan tulang pada embrio terjadi melalui dua cara, yaitu osteogenesis
desmalis dan osteogenesis enchondralis. Keduanya menyebabkan jaringan pendukung
kolagen primitive diganti oleh tulang, atau jaringan kartilago yang selanjutnya akan diganti
pula menjadi jaringan tulang. Hasil kedua proses osteogenesis tersebut adalah anyaman
tulang yang selanjutnya akan mengalami remodeling oleh proses resorpsi dan aposisi untuk
membentuk tulang dewasa yang tersusun dari lamella tulang. Kemudian, resorpsi dan
deposisi tulang terjadi pada rasio yang jauh lebih kecil untuk mengakomodasi perubahan
yang terjadi karena fungsi dan untuk mempengaruhi homeostasis kalsium. Perkembangan
tulang ini diatur oleh hormone pertumbuhan, hormone tyroid, dan hormone sex.
Osteogenesis Desmalis
Nama lain dari penulangan ini yaitu Osteogenesis intramembranosa, karena terjadinya
dalam membrane jaringan. Tulang yang terbentuk selanjutnya dinamakan tulang desmal.
Yang mengalami penulangan desmal ini yaitu tulang atap tengkorak. Mula-mula jaringan
mesenkhim mengalami kondensasi menjadi lembaran jaringan pengikat yang banyak
mengandung pembuluh darah. Sel-sel mesenkhimal saling berhubungan melalui tonjolan-
tonjolannya. Dalam substansi interselulernya terbentuk serabut-serabut kolagen halus yang
terpendam dalam substansi dasar yang sangat padat. Tanda-tanda pertama yang dapat dilihat
adanya pembentukan tulang yaitu matriks yang terwarna eosinofil di antara 2 pembuluh darah
yang berdekatan. Oleh karena di daerah yang akan menjadi atap tengkorak tersebut terdapat
anyaman pembuluh darah, maka matriks yang terbentuk pun akan berupa anyaman. Tempat
perubahan awal tersebut dinamakan Pusat penulangan primer.
Pada proses awal ini, sel-sel mesenkhim berdiferensiasi menjadi osteoblas yang
memulai sintesis dan sekresi osteoid. Osteoid kemudian bertambah sehingga berbentuk
lempeng-lempeng atau trabekulae yang tebal. Sementara itu berlangsung pula sekresi
molekul-molekul tropokolagen yang akan membentuk kolagen dan sekresi glikoprotein.
Sesudah berlangsungnya sekresi oleh osteoblas tersebut disusul oleh proses pengendapan
garam kalsium fosfat pada sebagian dari matriksnya sehingga bersisa sebagai selapis tipis
matriks osteoid sekeliling osteoblas. Dengan menebalnya trabekula, beberapa osteoblas akan
terbenam dalam matriks yang mengapur sehingga sel tersebut dinamakan osteosit. Antara sel-
sel tersebut masih terdapat hubungan melalui tonjolannya yang sekarang terperangkap dalam
kanalikuli. Osteoblas yang telah berubah menjadi osteosit akan diganti kedudukannya oleh
sel-sel jaringan pengikat di sekitarnya.
Dengan berlanjutnya perubahan osteoblas menjadi osteosit maka trabekulae makin
menebal, sehingga jaringan pengikat yang memisahkan makin menipis. Pada bagian yang
nantinya akan menjadi tulang padat, rongga yang memisahkan trabekulae sangat sempit,
sebaliknya pada bagian yang nantinya akan menjadi tulang berongga, jaingan pengikat yang
masih ada akan berubah menjadi sumsum tulang yang akan menghasilkan sel-sel darah.
Sementara itu, sel-sel osteoprogenitor pada permukaan Pusat penulangan mengalami mitosis
untuk memproduksi osteoblas lebih lanjut.
Osteogenesis Enchondralis
Awal dari penulangan enkhondralis ditandai oleh pembesaran khondrosit di tengah-
tengah diaphysis yang dinamakan sebagai pusat penulangan primer. Sel sel khondrosit di
daerah pusat penulangan primer mengalami hypertrophy, sehingga matriks kartilago akan
terdesak mejadi sekat-sekat tipis. Dalam sitoplasma khondrosit terdapat penimbunan
glikogen. Pada saat ini matriks kartilago siap menerima pengendapan garam garam kalsium
yang pada gilirannya akan membawa kemunduran sel-sel kartilago yang terperangkap karena
terganggu nutrisinya. Proses kerusakan ini akan mengurangi kekuatan kerangka kalau tidak
diperkuat oleh pembentukan tulang disekelilingnya. Pada saat yang bersamaan,
perikhondrium di sekeliling pusat penulangan memiliki potensi osteogenik sehingga di
bawahnya terbentuk tulang. Pada hakekatnya pembentukan tulang ini melalui penulangan
desmal karena jaringan pengikat berubah menjadi tulang. Tulang yang terbentuk merupakan
pipa yang mengelilingi pusat penulangan yang masih berongga rongga sehingga bertindeak
sebagai penopang agar model bentuk kerangka tidak terganggu. Lapisan tipis tulang tersebut
dinamakan pipa periosteal. Setelah terbentuknya pipa periosteal, masuklah pembuluh-
pembuluh darah dari perikhondrium,yang sekarang dapat dinamakan periosteum, yang
selanjutnya menembus masuk kedalam pusat penulangan primer yang tinggal matriks
kartilago yang mengalami klasifikasi. Darah membawa sel sel yang diletakan pada dinding
matriks. Sel-sel tersebut memiliki potensi hemopoetik dan osteogenik. Sel sel yang
diletakan pada matriks kartilago akan bertindak sebagai osteoblast. Osteoblas ini akan
mensekresikan matriks osteoid dan melapiskan pada matriks kartilago yang mengapur.
Selanjutnya trabekula yang terbentuk oleh matriks kartilago yang mengapur dan dilapisi
matriks osteoid akan mengalami pengapuran pula sehingga akhirnya jaringan osteoid berubah
menjadi jaringan tulang yang masih mengandung matriks kartilago yang mengapur di bagian
tengahnya. Pusat penulangan primer yang terjadi dalam diaphysis akan disusun oleh pusat
penulangan sekunder yang berlangsung di ujung ujung model kerangka kartilago.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang
1. Herediter (genetic)
Tinggi badan anak secara umum tergantung dari orangtua. Anak-anak yang dilahirkan dari
orangtua yang tinggi biasanya mempunyai badan yang tinggi juga.
2. Faktor nutrisi
Suplai bahan makan yang mengandung kalsium, fosfat, protein, dan vitamin A C D adalah
hal yang penting untuk generasi pertumbuhan tulang serta untuk memelihara rangka yang
sehat.
3. Factor-faktor endokrin
a. Paratiroid hormone(PTH)
Satu sama lain saling berlawanan dalam memelihara kadar kalsium darah sehingga
merangsang terjadinya PTH dengan cara:
-merangsang osteoplas reabsorbsi tulang dan melepas kalsium kedalam darah
-merangsang absorbsi kalsium dan fosfat dari usus
-meresorbsi kalsium dari tubulus renalis.
b. Tirokalsitonin
Tirokalsitonin adalah hormon yang dihasilkan sel-sel parafolikuler dari kelenjar tiroid. Cara
kerjanya menghambat resorbsi tulang.
c. Hormon pertumbuhan
Hormon ini dihasilkan hipofise anterior dan penting untuk proliferase (bertambah banyak)
secara normal dari rawan epifisealis untuk memelihara tinggi badan yang normal.
d. Tiroksin
Tiroksin bertanggung jawab dalam pertumbuhan tulang yang layak, remodeling tulang dan
kematangan tulang.
4. Faktor persarafan
Gangguan suplai persarafan mengakibatkan penipisan tulang seperti yang terlihat pada
kelaianan poliomyelitis.
5.Faktor mekanis.
Kekuatan dan arah dari tuberkula tulang ditentukan oleh gaya-gaya mekanis yang bekerja
padanya.
6.Penyakit-penyakit mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap pertumbuhan tulang.
Biologi tulang
Susunan tulang terdiri dari sel-sel, matrik organic, dan mineral. Mineral ini terdiri dari
kolagen dan bahan dasar yang mengandung monopolisakarida pada komponen matriks inilah
mengendapnya kristalloid yang terdiri dari kalsium dan fosfat.Sel-sel tulang terdiri dari
ostiosid, osteoblas, dan osteoklast. Setiap sel ini mempunyai fungsi khusus yang letaknya pun
berbeda-beda. Kristal tulang terdiri dari beberapa komponen atau bagian, yaitu:
a. Kristal bagian dalam (Kristal interior), terdiri dari ion-ion.
b. Permukaan Kristal (Kristal permukaan) mengandung kation dan anion yang spesifik.
c. Lapisan yang mengandung air (hidration shell) mengandung lapisan anion yang tidak
spesifik, selalu dalam keadaan seimbang dan dinamis dengan medium sekitarnya.
Komponen lain yang penting dalam tulang adalah glikogen. Glikogen mempunyai
deposisi garam-garam anorganik dalam tulang rawan tempat sel-sel tulang rawan mengalami
hipertrofi sehingga didapati kadar glikogen yang tinggi didaerah tersebut. Bila enzim-enzim
yang memegang peranan dalam siklus glikolisis dihambat kerjanya maka proses klasifikasi
juga terhambat. Dalam proses pertumbuhan dan pembentukan tulang terdapat 2 macam
proses:
- Osifikasi mendokondral
Setelah terbentuknya epifise yang masih dalam keadaan tulang rawan pertumbuhan
tulang ini ditandai dengan pertumbuhan tulang rawan dan degenerasi dalam epifise.
- Osifikasi membrane
Proses integrasi seluler pembentukan tulang baru di atas permukaan korteks telah
dibentuk terlebih dahulu pada saat terjadinya proses resorbsi tulang kedua, cara berlangsung
secara simultan. Proses pertama terjadi resorbsi matriksnya dan proses kedua berlangsung
pelarutan hidroksiapatik yang diikuti terbebasnya garam kalsium fosfat. Faktor yang paling
berperan adalah osteoklas yang dikenal sebagai pembuang tulang (sel perusak tulang) dan
mempunyai kemampuan fagosit. Osteoklas menghasilkan zat yang dapat menyebabkan
terjadinya depolimerisasi atau dibebaskannya garam-garam dan asam fosforik pada tulang
yang berakibat larutnya atau dibebaskannya kalsium dalam tulang.
Zat lain yang mempunyai kaitan dengan metabolism tulang adalah asam sitrat. Kadar
asam sitrat didapati lebih tinggi dikawasan korteks diafise dari tulang panjang bahan organik
yang cukup penting didalam pertumbuhan tulang adalah glikogen. Glikogen merupakan
bagian dari tulang rawan dan tulang yang sedang tumbuh. Bila dalam suatu proses klasifikasi
glikogen ditiadakan atau keaktifannya dicegah maka proses klasifikasi akan terhenti.
3.1.3 Penyembuhan Tulang
Kebanyakan patah tulang sembuh melalui osifikasi endokondral. Ketika tulang
mengalami cedera, fragmen tulang tidak hanya ditambal dengan jaringan parut. Namun
tulang mengalami regenerasi sendiri. Umumnya patah tulang sembuh melalui osifikasi
endokondral. Ketika tulang mengalami cidera, fragmen tulang tidak hanya ditambal dengan
jaringan parut, namun tulang mengalami regenerasi sendiri. Mengutip pendapat Smeltzer
(2002), tahapan penyembuhan tulang terdiri dari: inflamasi, proliferasi sel, pembentukan
kalus, penulangan kalus (osifikasi), dan remodeling.
Tahap Inflamasi.
Tahap inflamasi berlangsung beberapa hari dan hilang dengan berkurangnya
pembengkakan dan nyeri. Terjadi perdarahan dalam jaringan yang cidera dan pembentukan
hematoma di tempat patah tulang. Ujung fragmen tulang mengalami devitalisasi karena
terputusnya pasokan darah. Tempat cidera kemudian akan diinvasi oleh magrofag (sel darah
putih besar), yang akan membersihkan daerah tersebut. Terjadi inflamasi, pembengkakan dan
nyeri.
Tahap Proliferasi Sel.
Kira-kira lima hari hematom akan mengalami organisasi, terbentuk benang-benang fibrin
dalam jendalan darah, membentuk jaringan untuk revaskularisasi, dan invasi fibroblast dan
osteoblast. Fibroblast dan osteoklast (berkembang dari osteosit, sel endotel, dan sel
periosteum) akan menghasilkan kolagen dan proteoglikan sebagai matriks kolagen pada
patahan tulang. Terbentuk jaringan ikat fibrus dan tulang rawan (osteoid). Dari periosteum,
tampak pertumbuhan melingkar. Kalus tulang rawan tersebut dirangsang oleh gerakan mikro
minimal pada tempat patah tulang. Tetapi gerakan yang berlebihan akan merusak sruktur
kalus. Tulang yang sedang aktif tumbuh menunjukkan potensial elektronegatif.
Tahap Pembentukan Kalus.
Pertumbuhan jaringan berlanjut dan lingkaran tulang rawan tumbuh mencapai sisi lain
sampai celah sudah terhubungkan. Fragmen patahan tulang digabungkan dengan jaringan
fibrus, tulang rawan, dan tulang serat matur. Bentuk kalus dan volume dibutuhkan untuk
menghubungkan defek secara langsung berhubungan dengan jumlah kerusakan dan
pergeseran tulang. Perlu waktu tiga sampai empat minggu agar fragmen tulang tergabung
dalam tulang rawan atau jaringan fibrus. Secara klinis fargmen tulang tidak bisa lagi
digerakkan.
Tahap Penulangan Kalus (Osifikasi).
Pembentukan kalus mulai mengalami penulangan dalam dua sampai tiga minggu patah
tulang, melalui proses penulangan endokondral. Patah tulang panjang orang dewasa normal,
penulangan memerlukan waktu tiga sampai empat bulan. Mineral terus menerus ditimbun
sampai tulang benar-benar telah bersatu dengan keras. Permukaan kalus tetap bersifat
elektronegatif.
Tahap Menjadi Tulang Dewasa (Remodeling).
Tahap akhir perbaikan patah tulang meliputi pengambilan jaringan mati dan reorganisasi
tulang baru ke susunan struktural sebelumnya. Remodeling memerlukan waktu berbulan-
bulan sampai bertahun-tahun tergantung beratnya modifikasi tulang yang dibutuhkan, fungsi
tulang, dan pada kasus yang melibatkan tulang kompak dan kanselus stres fungsional pada
tulang. Tulang kanselus mengalami penyembuhan dan remodeling lebih cepat daripada
tulang kortikal kompak, khususnya pada titik kontak langsung.
Selama pertumbuhan memanjang tulang, maka daerah metafisis mengalami remodeling
(pembentukan) dan pada saat yang bersamaan epifisis menjauhi batang tulang secara
progresif. Remodeling tulang terjadi sebagai hasil proses antara deposisi dan resorpsi
osteoblastik tulang secara bersamaan. Proses remodeling tulang berlangsung sepanjang
hidup, dimana pada anak-anak dalam masa pertumbuhan terjadi keseimbangan (balance)
yang positif, sedangkan pada orang dewasa terjadi keseimbangan yang
negative. Remodeling juga terjadi setelah penyembuhan suatu fraktur.
3.2 Fisiologi Muskulus
3.2.1 Muskulus
Otot (musculus) merupakan suatu organ atau alat yang memungkinkan tubuh dapat
bergerak. Otot merupakan alat gerak aktif. Ini adalah suatu sifat yang penting bagi organisme.
Gerak sel terjadi karena sitoplasma mengubah bentuk. Pada sel-sel, sitoplasma ini merupakan
benang-benang halus yang panjang disebut miofibril. Kalau sel otot mendapat rangsangan
maka miofibril akan memendek. Dengan kata lain sel otot akan memendekkan dirinya kearah
tertentu (berkontraksi).
Sebagaian besar otot tubuh ini melekat pada kerangka, yang menyebabkan dapat
bergerak secara aktif sehingga dapat menggerakkan bagian-bagian kerangka dalam suatu
letak yang tertentu. Otot merupakan sebuah alat yang menguasai gerak aktif dan memelihara
sikap tubuh. Sedangkan rangka merupakan organ yang memberi bentuk tubuh untuk otot
melekat dan menghasilkan gerak.
Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari
600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-
tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan
kulit. Fungsi sistem muskuler/otot:
Pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan
bergerak dalam bagian organ internal tubuh.
Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan
mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap
gaya gravitasi.
Produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk
mepertahankan suhu tubuh normal.
Ciri-ciri sistem muskuler/otot:
Kontraksibilitas. Serabut otot berkontraksi dan menegang, yang dapat atau tidak
melibatkan pemendekan otot.
Eksitabilitas. Serabut otot akan merespons dengan kuat jika distimulasi oleh impuls
saraf.
Ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang
otot saat rileks.
Elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau
meregang.
Dalam garis besarnya sel otot dapat kita bagi menjadi tiga golongan, yaitu:
1. Otot motoritas, disebut juga otot serat lintang (otot lurik) oleh karena di dalamnya
protoplasma mempunyai garis-garis melintang. Pada umumnya otot ini melekat pada
kerangka sehingga disebut juga otot kerangka. Otot ini dapat bergerak menurut kemauan kita
(otot sadar), pergerakkanya cepat tetapi cepat lelah, rangsangan ini dialirkan melalui saraf
motoris.
2. Otot otonom, disebut juga otot polos karena protoplasmanya licin tidak mempunyai garis
melintang. Otot ini terdapat di alat-alat dalam seperti ventrikulus, usus, kandung kemih,
pembuluh darah, dan lain-lain, cara kerjanya diluar kesadaran kita (otot tak sadar) oleh
karena rangsangannya melalui saraf otonom.
Struktur Mikroskopis Otot Polos:
Sarcoplasmanya terdiri dari myofibril yang disusun oleh myofilamen-myofilamen.
3. Otot jantung, bentuknya menyerupai otot serat lintang, di dalam sel protoplasmanya
terdapat serabut-serabut melintang yang bercabang-cabang tetapi jika kita melihat fungsinya
seperti otot polos, dapat bergerak sendiri secara otomatis karena mendapat rangsangan dari
susunan saraf otonom. Otot ini hanya terdapat pada jantung yang mempunyai fungsi
tersendiri. Bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti, tapi otot jantung juga mempunyai
masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut.
Sebagian besar otot tubuh ini meleket pada kerangka, dapat bergerak secara aktif. Jadi
otot kerangka merupakan alat yang menguasai alat gerak aktif dan untuk memelihara sikap
tubuh. Dalam keadaan istirahat, keadaanya tidak kendur sama sekali, tapi mempunyai
ketegangan sedikit yang disebut tonus.
Susunan kerangka terdiri dari susunan berbagai macam tulang-tulang yang banyaknya
kira-kira 206 buah tulang yang satu sama lainnya saling berhubungan.
3.2.2 Mekanisme Sistem Musculusceletal
Kontraksi otot
Otot dapat berkontraksi dengan cepat, apabila ia mendapat rangsangan dari luar
berupa rangsangan arus listrik, rangsangan mekanis panas, dingin, dan lain-lain. Dalam
keadaan sehari-hari otot ini bekerja atau berkontraksi menurut perintah atau pengaruh yang
dating dari susunan saraf motoris.
Jenis kontraksi otot
Kontraksi isometric (panjang ukuran sama) adalah otot yang mempunyai unsur elastik
dan kental dalam rangkaian dengan mekanisme kontraktil, maka kontraksi timbul tanpa suatu
penurunan yang layak dalam panjang keseluruhan otot. Kontraksi otot yang kuat dan lama
mengakibatkan kelelahan otot. Sebagian besar kelelahan akibat dari ketidakmampuan proses
kontraksi dan metabolik serat otot untuk terus memberi hasil kerja yang sama dan akan
menurun setelah aktifitas otot mengurangi kontraksi otot lebih lanjut. Tiap otot dikelilingi
oleh jaringan yang merupakan selaput pembungkus yang disebut fasia. Fasia ini berfungsi
sebagai pembungkus, menahan dan melindungi otot agar tetap pada tempatnya, tempat
asal/origo dari beberapa otot dan tempat letaknya pembuluh darah dan saraf untuk jaringan
otot. Diantara urat otot dan tulang terdapat kandung lendir yang disebut juga mukosa bursa
yang di dalamnya berisi lendir yang berguna untuk melicinkan urat terhadap pergeseran
tulang, juga untuk memudahkan gerak otot terhadap kedudukan tulang. Retikulum, adalah
bagian yang padat dari fasia dalam dan mengikat tendo yang berjalan melalui pergelangan
mata kaki dan pergelangan tangan. Diafragma, struktur muskulus tendonium yang
memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen dan membentuk lantai dari rongga toraks
atau rongga abdomen.
Mekanisme kontraksi otot secara umum mulai dari timbul dan berakhirnya kontraksi
adalah sebagai berikut :
a) Potensial aksi berjalan sepanjang sebuah saraf motorik sampai ke ujung serat
saraf.
b) Setiap ujung seraf menyekresi substansi neurotransmitter yaitu asetilkolin dalam
jumlah sedikit.
c) Astilkolin bekerja untuk area setempat pada membran serat otot guna membuka
saluran asetilkolin melalui molekul-molekul protein dalam membran serat otot.
d) Terbukanya saluran asetilkolin memungkinkan sejumlah besar ion natrium
mengalir ke bagian dalam membran serat otot pada titik terminal saraf. Peristiwa ini
menimbulkan potensial aksi serat saraf.
e) Potensial aksi berjalan sepanjang membran saraf otot dengan cara yang sama
seperti potensial aksi berjalan sepanjang membran saraf.
f) Potensial aksi kana menimbulkan depolarisasi membran serat otot, berjalan dalam
serat otot ketika potensial aksi menyebabkan reticulum sarkoslema melepas sejumlah
ion kalsium, yang disimpan dalam reticulum ke dalam myofibril.
g) Ion kalsium menimbulkan kekuatan menarik antara filament aktin dan myosin
yang menyebabkan bergerak bersama-sama menghasilkan kontraksi.
h) Setelah kurang dari satu detik kalsium dipompakan kembali ke dalam reticulum
sarkoplasma tempat ion-ion disimpan sampai potensial aksi otot yang baru lagi.
3.2.3 Metabolisme Otot
Sumber energi otot adalah:
1. ATP + air ADP + asam fosfat + 1200 kal
2. Fosfokreatin + ADP kreatin + ATP
3. Oksidatif fosforilasi
40 ATP dari bahan dasar glukosa atau FFA.
Pada proses ini membutuhkan oksigen, namun proses ini membutuhkan waktu yang lama.
4. Glikolisis
Proses ini tanpa menggunakan oksigen 4 ATP dan asam laktat. Dan proses ini lebih cepat.
3.3 Fisiologi Persendian
Artikulasi atau sendi adalah hubungan antara dua tulang yang berdekatan sehingga
memungkinkan melakukan berbagai macam gerakan. Tulang-tulang ini dipadukan dengan
berbagai cara, misalnya dengan kapsul sendi, pita fibrosa, ligamen, tendon, fasia, atau otot.
Sendi diklasifikasikan sesuai dengan struktur (berdasarkan ada tidaknya rongga persendian
diantara tulang-tulang yang berartikulasi dan jenis jaringan ikat yang berhubungan dengan
persendian tersebut), dan menurut fungsi persendian (berdasarkan jumlah gerakan yang
mungkin dilakukan pada persendian.
a. Klasifikasi struktural persendian :
1. Sendi fibrosa
Tulang-tulang dihubungkan oleh serat-serat kolagen yang kuat. Sendi ini biasanya
terikat. Misalnya, sutura tulang tengkorak. Kadang sendi dapat sedikit bergerak.
2. Sendi kartilago
Permukaan tulang ditutupi oleh lapisan kartilago dan dihubungkan oleh jaringan
fibrosa kuat yang tertanam kedalam kartilago. Misalnya, antara korpus vertebra dan simfisis
pubis. Sendi ini biasanya memungkinkan gerakan sedikit bebas.
3. Sendi synovial
Sendi ini adalah jenis sendi yang paling umum. Sendi ini biasanya memungkinkan
gerakan yang bebas, (misalnya: lutut, bahu, siku, pergelangan tangan, dll) tetapi beberapa
sendi synovial secara relative tidak bergerak (misalnya: sendi sakroiliaka). Sendi ini
dibungkus dalam kapsul fibrosa dibatasi dengan membran synovial tipis. Membran ini
menskresi cairan synovial kedalam ruang sendi untuk melumasi sendi. Permukaan tulang
dilapisi dengan kartilago artikular halus dan keras dimana permukaan ini berhubungan
dengan tulang. Pada beberapa sendi terdapat satu sabit kartilago fibrosa yang sebagian
memisahkan tulang-tulang sendi (misalnya: lutut dan rahang).
b. Klasifikasi fungsional persendian:
1) Sendi sinartrosis atau sendi mati merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan
misalnya pada persambungan tulang tengkorak.. Secara struktural, persendian ini dibungkus
dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago.
2) Sutura adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa rapat dan hanya
ditemukan pada tulang tengkorak.
3) Sinkondrosis adalah sendi yang tulang-tulangnya dihubungkan dengan kartilago hialin.
4) Amfiartrosis adalah sendi dengan pergerakan terbatas yang memungkinkan terjadinya
sedikit gerakan sebagai respons terhadap torsi dan kompresi.
5) Simfisis adalah sendi yang kedua tulangnya dihubungkan dengan diskus kartilago,yang
menjadi bantalan sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan.
6) Gomposis adalah sendi dimana tulang berbentuk kerucut masuk dengan pas dalam
kantong tulang, seperti pada gigi yang tertanam pada alveoli.
7) Diartrosis adalah sendi yang bergerak bebas, disebut juga sendi synovial. Sendi ini
memiliki rongga sendi yang berisi cairan synovial, suatu kapsul sendi (artikular) yang
menyambung kedua tulang, dan ujung tulang pada sendi synovial dilapisi kartilago artikular.
Ciri ciri sendi diartrosis:
Pada setiap sendi bagian ujung sendi ditutupi oleh tulang rawan hialin yang halus, dilapisi
oleh selubung fibrus kapsul sendi
Kapsul dilapisi oleh membran sinovial yang mensekresi cairan pelumas dan peredam
getaran dalam kapsul sendi (cairan synovial), sehingga tidak terjadi kontak/sentuhan antar
permukaan tulang
Untuk membentuk sendi maka antartulang dihubungkan dengan ligamen (pita jaringan
ikat fibrus)
Ligamen dan tendon otot yang melintasi sendi sehingga menjaga kestabilan sendi
Jenis jenis sendi diartrosis
Sendi Peluru
Kepala sendi yang bulat tepat masuk di dalam rongga cawan sendi sehingga memungkinkan
gerakan bebas penuh. Contoh: Sendi panggul dan bahu
Sendi Engsel/Hinge
Sumbu gerak tegak lurus pada arah panjang tulang sehingga arah gerak hanya pada satu arah.
Contoh: Siku dan lutut
Sendi Pelana
Permukaan sendi berbentuk pelana, arah sumbu yang satu permukaan cembung dalam arah
sumbu yang lain cembung. Contoh: Pada dasar ibu jari
Sendi Pivot / Kisar
Gerakan rotasi sesuai dengan arah panjang tulang untuk melakukan aktivitas.
Contoh: Sendi antara radius dan ulna (untuk membuka pintu)
Sendi Peluncur
Gerakan ke semua arah dan contohnya adalah sendi-sendi tulang karpalia di pergelangan
tangan.
Sendi Kondiloid
Mirip sendi engsel, tetapi dapat bergerak dalam dua bidang, lateral ke belakang dan ke depan
sehingga flexi, extensi, abduksi, adduksi (ke samping) Contoh: Temporomandibula
3.4 Fisiologi Penyokong
Jaringan penyokong disebut juga jaringan penguat atau jaringan penunjang. Yang
termasuk jaringan penguat atau penyokong adalah :
1. Jaringan Ikat
2. Jaringan Tulang Rawan (Kartilago)
3. Jaringan Tulang
4. Jaringan Darah
5. Jaringan Limfe/Getah Bening
Namun yang akan dibahas sekarang adalah tentang jaringan ikat.
3.4.1 Jaringan Ikat
Jaringan ikat terdiri dari serabut, sel-sel, dan cairan ekstra seluler. Cairan ekstra
seluler dan serabut disebut matriks. Fungsi jaringan ikat adalah mengikat atau
mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan berbagai organ menjadi sistem organ,
menjadi selubung organ dan melindungi jaringan atau organ tubuh.
Berdasarkan struktur dan fungsinya jaringan ikat dibedakan menjadi dua:
a. Jaringan ikat longgar
Ciri-ciri: sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks yang
mengandung serabut kolagen dan serabut elastis. Jaringan ikat longgar terdapat di sekitar
organ-organ, pembuluh darah dan saraf.
Fungsinya untuk membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf.
b. Jaringan ikat padat
Nama lainnya jaringan ikat serabut putih, karena terbuat dari serabut kolagen yang berwarna
putih. Jaringan ini terdapat pada selaput urat, selaput pembungkus otot, fasia, ligamen dan
tendon.
Fasia adalah jaringan ikat berbentuk lembaran yang menyelimuti otot.
Ligamen adalah jaringan ikat yang berperan sebagai penghubung antar tulang.
Tendon adalah ujung otot yang melekat pada tulang.
Fungsinya untuk menghubungkan berbagai organ tubuh seperti otot dengan tulang-tulang,
tulang dengan tulang, juga memberikan perlindungan terhadap organ tubuh.
3.4.2 Ligamen dan Tendon
Pada dasarnya, tendon dan ligament termasuk jaringan penghubung yang berserat.
Tendon dan ligament berperan penting dalam pergerakan otot. Hal itu berkaitan dengan
fungsi tendon dan ligament itu sendiri. Tendon membantu terjadinya pergerakan sendi
dengan mentransmisikan gaya mekanik (tekanan) dari otot ke tulang. Ligament berfungsi
sebagai penghubung antar tulang dan memberikan stabilitas pada sendi. Tidak seperti otot,
yang merupakan jaringan aktif dan bisa menghasilkan gaya mekanik, tendon dan ligament
termasuk jaringan pasif yang tidak bisa berkontraksi untuk menghasilkan gaya. Ligamen dan
tendon tersusun dari jaringan konektif fibrosa yang tebal, mengandung serabut kolagen dalam
jumlah yang sangat besar.
a. Ligamen
Ligamen adalah jaringan ikat fibrosa yang sedikit lentuk, yang mengikat satu tulang
dengan tulang lainnya dan membentuk sendi. Ligamen mengendalikan jangkauan gerak
sendi, mencegah dan menstabilkan sendi sehingga tulang bergerak dalam keselarasan. Karena
memiliki kemampuan peregangan terbatas, ligamen membatasi panjang gerak sendi untuk
melindunginya dari cedera.
b. Tendon
Tendon adalah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan otot dengan tulang. Setiap
otot punya tendon di ujung-ujungnya. Tendon memiliki kemampuan meregang yang sangat
kecil. Tugas tendon adalah untuk mengirimkan daya di antara tulang dan otot. Pada dasarnya
tendonlah yang memungkinkan kita bergerak karena tendon adalah perantara ketika otot
menggerakkan tulang. Dibandingkan dengan otot, tendon lebih kaku, mempunyai kekuatan
tarik lebih besar, dan dapat menahan tegangan yang lebih besar. Oleh karena itu, disekitar
pergerakan dimana ruangnya terbatas, kerja sama otot ke tulang dibuat oleh tendon. Tendon
mampu menahan beban yang sangat besar dengan deformasi yang sangat kecil. Sifat tendon
ini memungkinkan otot untuk mentransmisikan gaya ke tulang tanpa menghabiskan energi
untuk regangan tendon.
Otot, tendon, dan ligamen juga bisa cedera sebagai akibat dari tekanan langsung, kerja
berlebihan, ataupun teregang terlalu jauh. Cedera bisa berupa sobekan parsial ataupun penuh.
Cedera seperti ini umum terjadi pada aktivitas olahraga intensitas tinggi dan memerlukan
perawatan untuk menghindari masalah kronis. Tendon, ligamen dan otot dapat diregangkan
dan diperkuat untuk menghindari cedera. Penyembuhan cedera pada jaringan ikat seperti
ligamen dan tendon akan memakan waktu yang sangat lama, bahkan kadang-kadang
memerlukan operasi. Walau dengan operasi dan terapi fisik, ligamen yang pernah cedera
cenderung menjadi kurang fleksibel, dan lebih rentan untuk cedera lagi.
Daftar Pustaka
Ashari, Ristyan. 2011. Anatomi dan fisiologi.
http://tyanystervokerz.blogspot.com/2011/06/anatomi-dan-fisiologi.html. 24 Maret
2013.
Hariyanto, Guruh. 2011. Biokimia Tendon Dan Ligamen.
http://guruhdanhariyanto.blogspot.com/2011/07/biomekanika-tendon-dan-
ligamen.html. 25Maret 2013.
Nia. 2012. Makalah Anatomi Fisiologi Sistem.
http://ukhtiniaumagapi.blogspot.com/2012/04/makalah-anatomi-fisiologi-sistem.html.
25 Maret 2013.
Syaifuddin. 2009. Fisiologi Tubuh Manusia Untuk Mahasiswa Keperawatan. Jakarta:
Salemba Medika.
Anda mungkin juga menyukai
- SAP Gout ArtritisDokumen10 halamanSAP Gout ArtritisAnnisa WahyuningsihBelum ada peringkat
- LP LipomaDokumen6 halamanLP LipomaAnnisa Wahyuningsih100% (2)
- Tugas Jurnal PesekDokumen42 halamanTugas Jurnal PesekAnnisa WahyuningsihBelum ada peringkat
- LP Dan Askep DMDokumen24 halamanLP Dan Askep DMAnnisa Wahyuningsih100% (1)
- Jurnal Konsep DiriDokumen17 halamanJurnal Konsep DiriAnnisa Wahyuningsih100% (2)
- Tugas Kep KeluargaDokumen10 halamanTugas Kep KeluargaAnnisa WahyuningsihBelum ada peringkat
- Tugas JurnalDokumen43 halamanTugas JurnalAnnisa WahyuningsihBelum ada peringkat
- WOC Tumor sereBRIDokumen1 halamanWOC Tumor sereBRIAnnisa Wahyuningsih0% (1)
- Pathway GlomerulonefritisDokumen1 halamanPathway GlomerulonefritisMelli Anna Jhaa71% (7)
- Woc GGKDokumen1 halamanWoc GGKAnnisa WahyuningsihBelum ada peringkat
- Woc OtosklerosisDokumen1 halamanWoc OtosklerosisAnnisa WahyuningsihBelum ada peringkat
- WOC BILIrubinDokumen1 halamanWOC BILIrubinAnnisa WahyuningsihBelum ada peringkat
- MAKALAH TEORI FLORENCE NIGHTINGALE (Gabung)Dokumen31 halamanMAKALAH TEORI FLORENCE NIGHTINGALE (Gabung)Annisa Wahyuningsih86% (7)
- WOC Striktur Uretra (Repaired)Dokumen2 halamanWOC Striktur Uretra (Repaired)Annisa Wahyuningsih67% (3)
- Woc AnemiaDokumen1 halamanWoc AnemiaAnnisa WahyuningsihBelum ada peringkat
- Woc Kanker KolonDokumen3 halamanWoc Kanker KolonAnnisa Wahyuningsih100% (7)
- Makalah Konsep Dasar KesehatanDokumen14 halamanMakalah Konsep Dasar KesehatanAnnisa Wahyuningsih100% (1)
- Makalah Psikologi BerfikirDokumen14 halamanMakalah Psikologi BerfikirAnnisa Wahyuningsih80% (5)
- Konsep HolistikDokumen11 halamanKonsep HolistikAnnisa WahyuningsihBelum ada peringkat