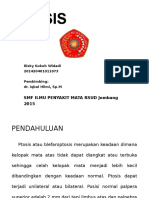Bab 1-5 Peb
Bab 1-5 Peb
Diunggah oleh
Iqbal Margi SyafaatJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Bab 1-5 Peb
Bab 1-5 Peb
Diunggah oleh
Iqbal Margi SyafaatHak Cipta:
Format Tersedia
1
BAB 1
PENDAHULUAN
Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyulit kehamilan dan merupakan
salah satu dari tiga penyebab tertinggi mortalitas dan morbiditas ibu bersalin.
Hipertensi dalam kehamilan meliputi hipertensi kronik yang timbul sebelum usia
kehamilan 20 minggu, preeklamsia, eklamsia, hipertensi kronik dengan
superimposed preeklamsia dan hipertensi gestasional Hadijanto, 2009).
Preeklamsia merupakan hipertensi yang timbul setelah usia kehamilan 20
minggu kehamilan disertai dengan proteinuri. Preeklampsia berat merupakan
kondisi spesifik dalam kehamilan, ditandai dengan peningkatan tekanan darah
(TD), proteinuria dan adanya sembab (edema) pada kehamilan setelah 20 minggu
atau segera setelah persalinan. Temuan yang paling penting adalah hipertensi, ibu
dengan preeklampsia berat memiliki tekanan darah sistolik 160mmHg dan
diastolik 110mmHg. Preeklamsia merupakan penyulit kehamilan yang akut dan
dapat terjadi ante, intra, dan postpartum (Hadijanto, 2009).
Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2008, angka kejadian
preeklampsia di seluruh dunia berkisar antara 0,51%-38,4%. Preeklamsia
diseluruh dunia diperkirakan menjadi penyebab kira-kira 14%(50.000-75.000)
kematian maternal setiap tahunnya (Hak Lim, 2009). Angka kejadian preeklamsia
di Amerika Serikat kira-kira 5% dari semua kehamilan, dengan gambaran
insidensinya 23 kasus preeklamsia ditemukan per 1000 kehamilan setiap tahunnya
(Joseph et al, 2008).
Pada tahun 2005, Angka Kematian Maternal (AKM) di rumah sakit seluruh
Indonesia akibat eklampsia atau preeklampsia sebesar 44,91%. Di Surabaya,
diperkirakan kematian akibat preeklampsia-eklampsia pada ibu mencapai 20%
dan kematian perinatal berkisar 28% (Bahari, 2009).
Preeklamsia dan merupakan salah satu penyebab kematian dan kesakitan ibu
dan bayi di seluruh dunia (Luca et al, 2008). Preeklamsia terjadi pada 5%
kehamilan dan lebih sering ditemukan pada kehamilan pertama dan pada wanita
yang sebelumnya menderita tekanan darah tinggi (Cunningham, 2006).
Ttingginya angka kejadian preeklamsia di Indonesia juga sangat mempengaruhi
kondisi janin dan perinatal. Penyebab terbesar kematian dan kesakitan ibu pada
preeklamsia adalah abrasion plasenta, edema pulmonar, kegagalan ginjal dan
hepar, miokardial infark, disseminated intravascular coagulation (DIC),
pedarahan serebral (Gilbert & Harmon, 2005). Sedangkan efek preeklamsia pada
fetal dan bayi baru lahir adalah insufisiensi plasenta, asfiksia neonatorum, intra
uterine growth retardation (IUGR), prematur, abrasion plasenta, berat badan lahir
rendah dan kematian janin (Gibson, 2007).
Pengelolaan preeklamsia berat mencakup pencegahan kejang, pengelolaan
hipertensi, pengelolaan cairan, pelayanan suportif terhadap penyulit organ yang
terlibat, dan saat yang tepat untuk persalinan. Perawatan preeklamsia berat dibagi
menjadi dua unsur, yaitu terhadap penyakitnya dengan pemberian obat-obat atau
terapi medisinalis dan sikap terhadap kehamilan berupa manajemen agresif,
terminasi setiap saat bila keadaan hemodinamika sudah stabil (Hadijanto, 2009).
Pengamatan yang cermat terhadap beberapa indikator prediksi preeklamsia,
dapat mengurangi angka kematian ibu dan janin yang dikandung. Hal ini meliputi
sistem perencanaan kehamilan, perawatan antenatal secara teratur dan efektif
selama periode kehamilan hingga keputusan untuk memilih metode melahirkan
yang terbaik apabila dijumpai kelainan hipertensi dalam kehamilan.
BAB 2
LAPORAN KASUS
2.1 Identitas
-
Nama Pasien
: Ny. K
Umur
: 34 tahun
Jenis kelamin
: perempuan
Agama
: Islam
Pekerjaan : Guru
- Alamat
: Jl. Teuku Umar VI no 297 RT4 RW4 Pandian Sumenep,
Madura
- Nama Suami : Tn. U
- Usia
-
: 35 tahun
Tanggal masuk : 28 April 2015
2.2
Anamnesis
1.
Keluhan utama
Kenceng-kenceng
2.
Riwayat penyakit sekarang
Pasien hamil anak ketiga datang ke IGD RSML pukul 01:25 WIB. Pasien
mengatakan sudah terasa kenceng-kenceng sejak 2 minggu yang lalu
Kenceng-kenceng dirasakan setiap hari sering namun tidak teratur.
Kenceng-kencenng dirasakan semakin sering sejak 3 hari ini. Kencengkenceng tidak disertai keluarnya darah lendir. Nyeri di bagian bawah perut
dan dibagian punggung sejak 3 hari ini. Belum ada air yang merembes dari
jalan lahir. Pasien juga mengeluh seluruh badan terasa bengkak, terutama di
bagian kaki. Sesak napas (+), pusing (-), pandangan kabur (-), nyeri ulu hati
(-). BAK dan BAB tidak ada keluhan. Tanggal 23 April 2015 lalu pasien
periksa ke laboratorium dan hasilnya adalah protein urin +4, kemudian dari
hasil pemeriksaan Lab di RSML diketahui protein urin +3. HPHT: 28 Juli
2014. TP: 4 Mei 2015.
3.
Riwayat penyakit dahulu
Hipertensi -, diabetes mellitus -, hipertensi saat kehamilan -, GDA pasien
pernah tinggi >200 mg/dl
4.
Riwayat penyakit kelurga
Tidak ada yang pernah menderita hipertensi saat hamil. Tidak ada riwayat
darah tinggi dan diabetes mellitus di keluarga
5.
Riwayat obstetri
1. Aterm/spt/bidan/RS/2800 gram/pr/11 th
2. Aterm/SC/RS/3000 gram/pr/6 th
3. Hamil ini
6.
Riwayat ginekologi
Menarche usia 12 tahun, siklus haid teratur, lama haid 7 hari, jumlah
normal, nyeri haid -, menopause -, keputihan + (putih bening, tidak gatal
dan tidak berbau).
7.
Riwayat perkawinan
Menikah 1 kali, lama menikah 12 tahun
8.
Riwayat kontrasepsi
IUD selama 5 tahun
2.3 Pemeriksaan Fisik
1.
2.
Vital sign
-
Keadaan umum : cukup baik
Kesadaran
: kompos mentis
Tekanan darah
: 158/94 mmHg
Nadi
: 84 x/menit
Nafas
: 32 x/menit
Suhu
: 36,5 oC
Status generalis
a.
Kepala-leher
o Mata
: konjungtiva anemis -/-, sklera ikterus -/-, pupil isokor 3
mm, refleks pupil +
o Mulut : bibir sianosis -, bercak-bercak putih pada rongga mulut o Leher : massa -, pembesaran KGB b.
Thoraks
o Inspeksi : bentuk dada normal , pergerakan dinding dada simetris
kanan dan kiri
o Palpasi : massa -, nyeri tekan o Perkusi: sonor di kedua lapang paru
o Auskultasi : suara nafas vesikuler, bunyi tambahan -, suara jantung
I/II tunggal, reguler, murmur -, gallop -
c.
Abdomen
o
o
o
o
Inspeksi : gravid, linea nigra +, striae gravidarum +
Auskultasi : bising usus + normal
Palpasi : soepel, hepar/lien tidak teraba, nyeri Perkusi : redup
d. Ekstremitas
o Edema +/+, akral hangat kering merah, CRT <2 detik
3.
Pemeriksaan obsetri
Leopold I
: TFU 34 cm, teraba bagian lunak dan tidak melenting pada
goyangan, kesan bokong
Leopold II
: Punggung di bagian kanan, DJJ 151x/mnt
Leopold III : Teraba bulat keras kesan kepala, belum masuk PAP, masih
bisa digoyangkan
Leopold IV
: 5/5, konvergen
VT Obsetri: belum ada pembukaan
2.4 Pemeriksaan Penunjang
1.
Laboratorium
Jenis Pemeriksaan
Hematologi
Leukosit
Neutrofil
Limfosit
Monosit
Eosinofil
Basofil
Eritrosit
Hemoglobin
Hematokrit
MCV
MCH
MCHC
RDW
Trombosit
MPV
LED 1 jam
LED 2 jam
Protein
Hasil
5200
67,2
15,4
3,2
0
0
4.800.000
10,3
32,7
73,8
28.5
34,2
14
239.000
6
64
82
+4
Nilai Normal
4.000 11.000
49 67
25 33
37
12
01
3.800.000 5.300.000
13 18
35 47
87 100
28 36
31 37
10 16
150.000 -450.000
5 10
01
17
2.5 Diagnosis
GIIIP2002A000 T/H UK 39-40 mgg + PEB
2.6 Penatalaksanaan
-Beri O2 4-6 liter/menit
-Infus RL 1500 cc/24 jam
-Kateterisasi urin untuk pengeluaran proteinuria
-Antikonvulsan
Dosis awal: MgSO4 4 gr IV sebagai larutan 20 % selama 5 menit, masukkan
melalui bolus pelan. Diikuti dengan MgSO4 (50%) 5 gr IM dengan 1 ml
lignokain 2% (dalam spuit yang sama)
Dosis pemeliharaan
MgSO4(50%) 5 g+lignokain 2 % 1 ml IM setiap 4 jam
Lanjutkan sampai 24 jam pasca persalinan atau kejang terakhir
-Hidralazin 5 mg IV pelan-pelan selama 5 menit sampai tekanan darah turun
2.7 Monitoring
- Keluhan pasien
- Vital sign (TD, nadi, suhu, RR)
- DJJ
- Auskultasi paru (memantau tanda-tanda edema paru)
- Tanda-tanda kemajuan persalinan (Pembukaan, Penurunan, Penipisan,
penyusupan, Ubun-ubun, denominantor)
- Produksi urin
- DL, LFT, RFT
BAB 3
TINJAUAN PUSTAKA
3.1 Definisi Preeklamsia
Preeklamsia-eklamsia merupakan kesatuan penyakit yang langsung
disebabkan oleh kehamilan.
Definisi preeklamsia adalah
hipertensi disertai
proteinuria dan edema akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau
segera setelah persalinan. Gejala ini dapat timbul sebelum 20 minggu bila terjadi
penyakit trofoblastik (Wibowo B., Rachimhadi T., 2008). Preeklamsia merupakan
suatu sindrom spesifik kehamilan dengan penurunan perfusi pada organ-organ
akibat vasospasme dan aktivasi endotel. Proteinuria adalah tanda yang penting
dari preeklamsia (Cunningham F. G., 2008). Preeklamsia adalah keadaan dimana
hipertensi disertai dengan proteinuria, edema atau keduanya, yang terjadi akibat
kehamilan setelah minggu ke-20, atau kadang-kadang timbul lebih awal bila
terdapat perubahan hidatidiformis yang luas pada vili khorialis (Cunningham F.G.,
2010).
Preeklampsia berat ialah preeklampsia dengan tekanan darah sistolik 160
mmHg dan tekanan darah diastolik 110 mmHg disertai proteinuria 5 g/ 24 jam
atau kualitatif 4+. Sedangkan pasien yang sebelumnya mengalami preeclampsia
kemudian disertai kejang dinamakan eklampsia (Wibowo B., Rachimhadi T.,
2008).
Penggolongan
preeclampsia
menjadi
preeclampsia
ringan
dan
preeclampsia berat dapat menyesatkan karena preeclampsia ringan dalam waktu
yang relative singkat dapat berkembang menjadi preeclampsia berat (Cunningham
F. G., 2008).
Preeklampsia berat dibagi menjadi:
a) Preeklampsia berat tanpa impending eclampsia
b) Preeklampsia berat dengan impending eclampsia.
10
Disebut impending eclampsia bila preeklampsia berat disertai gejala-gejala
subjektif berupa :
Muntah-muntah
Sakit kepala yang keras karena vasospasm atau oedema otak
Nyeri epigastrium karena regangan selaput hati oleh haemorrhagia atau
oedema, atau sakit karena perubahan pada lambung.
3.2 Insidensi Preeklampsia
Frekuensi
banyak
faktor
ekonomi,
preeklampsia
untuk
tiap
negara
berbeda-beda
karena
yang mempengaruhinya; jumlah primigravida, keadaan sosial
perbedaan kriteria dalam penentuan diagnosis dan
Indonesia frekuensi kejadian preeklampsia sekitar 3-10% ,
lain-lain.
Di
Sedangkan
di
Amerika Serikat dilaporkan bahwa kejadian preeklampsia sebanyak 5% dari
semua kehamilan (23,6 kasus per 1.000 kelahiran). Pada primigravida frekuensi
preeklampsia lebih tinggi bila dibandingkan dengan multigravida,
primigravida muda. Diabetes melitus, mola hidatidosa,
kehamilan
terutama
ganda,
hidrops fetalis, umur lebih dari 35 tahun dan obesitas merupakan faktor
predisposisi untuk terjadinya preeclampsia (Suyono, Y.J., 2008).
Di
Surjadi,
samping
itu,
preklamsia
juga
dipengaruhi
oleh
paritas.
mendapatkan angka kejadian dari 30 sampel pasien preeklampsia di
RSU Dr. Hasan Sadikin. Bandung paling banyak terjadi pada ibu dengan paritas
1-3 yaitu sebanyak 19 kasus dan juga paling banyak terjadi pada usia kehamilan
diatas 37 minggu yaitu sebanyak 18 kasus (Cunningham F.G., 2010). Wanita
dengan kehamilan kembar bila dibandingkan dengan kehamilan tunggal, maka
memperlihatkan insiden hipertensi gestasional (13 % : 6 %) dan preeklampsia (13
% : 5 %) yang secara bermakna lebih tinggi. Selain itu, wanita dengan kehamilan
11
kembar memperlihatkan prognosis neonatus yang lebih buruk daripada wanita
dengan kehamilan tunggal (Cunningham F.G., 2010).
3. 3 Etiologi Preeklampsia
Penyebab preeklamsia/eklamsia sampai sekarang belum diketahui secara
pasti. Banyak teori yang menerangkan namum belum dapat memberi jawaban
yang memuaskan. Teori yang dewasa ini banyak dikemukakan adalah iskemia
plasenta. Namun teori ini tidak dapat menerangkan semua hal yang berkaitan
dengan kondisi ini. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor yang
menyebabkan terjadinya preeklamsia/eklamsia (Wibowo B., Rachimhadi T.,
2008).
Ada beberapa teori mencoba menjelaskan perkiraan etiologi dari kelainan
tersebut di atas, sehingga kelainan ini sering dikenal sebagai the diseases of theory
(Sudhaberata K., 2008). Adapun teori-teori tersebut antara lain:
1) Peran Prostasiklin dan Tromboksan
Pada preeklamsia/eklamsia didapatkan kerusakan pada endotel vaskuler,
sehingga terjadi penurunan produksi prostasiklin (PGI2) yang pada kehamilan
normal meningkat, aktivasi penggumpalan dan fibrinolisis, yang kemudian akan
diganti dengan trombin dan plasmin. Trombin akan mengkonsumsi antitrombin III
sehingga terjadi deposit fibrin. Aktivasi trombosit menyebabkan pelepasan
tromboksan (TxA2) dan serotonin, sehingga terjadi vasospasme dan kerusakan
endotel.
2) Peran Faktor Imunologis
Preeklamsia/eklamsia sering terjadi pada kehamilan pertama dan tidak
timbul lagi pada kehamilan berikutnya. Hal ini dapat diterangkan bahwa pada
kehamilan pertama pembentukan blocking antibodies terhadap antigen plasenta
tidak sempurna, yang semakin sempurna pada kehamilan berikutnya. Fierlie F.M.
12
(1992) mendapatkan beberapa data yang mendukung adanya sistem imun pada
penderita preeklamsia / eklamsia:
a) Beberapa wanita dengan preeklamsia/eklamsia mempunyai kompleks
imun dalam serum.
b) Beberapa studi juga mendapatkan adanya aktivasi sistem komplemen
pada preeklamsia/eklamsia diikuti dengan proteinuria.
3) Peran Faktor Genetik / familial
Beberapa bukti yang menunjukkan peran faktor genetik pada kejadian
preeklamsia / eklamsia antara lain:
a) Preeklamsia / eklamsia hanya terjadi pada manusia.
b) Terdapatnya kecenderungan meningkatnya frekuensi preeklamsia /
eklamsia pada anak-anak dari ibu yang menderita preeklamsia /
eklamsia.
c) Kecenderungan meningkatnya frekuensi preeklamsia / eklamsia pada
anak dan cucu ibu hamil dengan riwayat preeklamsia/eklamsia dan
bukan pada ipar mereka.
d) Peran Renin-Angiotensin-Aldosteron System (RAAS).
3.4 Faktor Risiko Preeklamsia
Faktor risiko preeklamsia meliputi kondisi medis yang berpotensi
menyebabkan kelainan mikrovaskular, seperti diabetes melitus, hipertensi kronis
dan kelainan vaskular serta jaringan ikat, sindrom antibodi fosfolipid dan
nefropati. Faktor risiko lain berhubungan dengan kehamilan itu sendiri atau dapat
spesifik terhadap ibu atau ayah dari janin (Sunaryo R., 2008).
Berbagai faktor risiko preeklamsia (Wibowo B., Rachimhadi T., 2009) :
1) Faktor yang berhubungan dengan kehamilan
a) Kelainan kromosom
13
b) Mola hydatidosa
c) Hydrops fetalis
d) Kehamilan multifetus
e) Inseminasi donor atau donor oosit
f) Kelainan struktur kongenital
2) Faktor spesifik maternal
a) Primigravida
b) Usia > 35 tahun
c) Usia < 20 tahun
d) Ras kulit hitam
e) Riwayat preeklamsia pada keluarga
f) Nullipara
g) Preeklamsia pada kehamilan sebelumnya
h) Kondisi medis khusus : diabetes gestational, diabetes tipe 1, obesitas,
hipertensi kronis, penyakit ginjal, trombofilia
i) Stress
3) Faktor spesifik paternal
a) Primipatemitas
b) Patner pria yang pernah menikahi wanita yang kemudian hamil dan
mengalami preeklamsia
3.5 Patofisiologi Preeklamsia
Pada preeklampsia yang berat dan eklampsia dapat terjadi perburukan
patologis pada sejumlah organ dan sistem yang kemungkinan diakibatkan oleh
vasospasme dan iskemia (Cunningham F. G., 2008). Wanita dengan hipertensi
pada kehamilan dapat mengalami peningkatan respon
substansi
endogen
(seperti
prostaglandin,
terhadap berbagai
tromboxan) yang dapat
14
menyebabkan vasospasme dan agregasi platelet. Penumpukan trombus dan
pendarahan dapat mempengaruhi sistem saraf pusat yang ditandai dengan sakit
kepala dan defisit saraf lokal dan kejang. Nekrosis ginjal dapat menyebabkan
penurunan
laju
filtrasi
glomerulus
dan proteinuria. Kerusakan hepar dari
nekrosis hepatoseluler menyebabkan nyeri epigastrium dan peningkatan tes fungsi
hati.
Manifestasi
terhadap
kardiovaskuler
intravaskular, meningkatnya cardiac
pembuluh
anemia
perifer. Peningkatan
dan
trombositopeni.
meliputi
output dan
hemolisis
penurunan
peningkatan
microangiopati
volume
tahanan
menyebabkan
Infark plasenta dan obstruksi plasenta
menyebabkan pertumbuhan janin terhambat bahkan kematian janin dalam rahim
(Wibowo B., Rachimhadi T., 2008).
Perubahan pada organ-organ :
1) Perubahan kardiovaskuler.
Gangguan fungsi kardiovaskuler yang parah sering terjadi pada preeklampsia
dan eklamsia. Berbagai gangguan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan
peningkatan afterload jantung akibat hipertensi, preload jantung yang secara
nyata dipengaruhi oleh berkurangnya secara patologis hipervolemia kehamilan
atau yang secara iatrogenik ditingkatkan oleh larutan onkotik atau kristaloid
intravena,
dan aktivasi endotel
disertai
ekstravasasi
ke dalam ruang
ektravaskular terutama paru (Cunningham F. G., 2008).
2) Metabolisme air dan elektrolit
Hemokonsentrasi yang menyerupai preeklampsia dan eklamsia tidak diketahui
penyebabnya. Jumlah air dan natrium dalam tubuh lebih banyak pada penderita
preeklampsia dan eklamsia daripada pada wanita hamil biasa atau penderita
dengan hipertensi kronik. Penderita preeklampsia tidak dapat mengeluarkan
dengan sempurna air dan garam yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh
15
filtrasi glomerulus menurun, sedangkan penyerapan kembali tubulus tidak
berubah. Elektrolit, kristaloid, dan protein tidak menunjukkan perubahan yang
nyata pada preeklampsia. Konsentrasi kalium, natrium, dan klorida dalam
serum biasanya dalam batas normal (Cunningham F. G., 2008).
3) Mata
Dapat dijumpai adanya edema retina dan spasme pembuluh darah. Selain itu
dapat terjadi ablasio retina yang disebabkan oleh edema
intra-okuler dan
merupakan salah satu indikasi untuk melakukan terminasi kehamilan. Gejala
lain yang menunjukan tanda preklamsia berat yang mengarah pada eklamsia
adalah adanya
skotoma, diplopia, dan ambliopia. Hal ini disebabkan
oleh adanya perubahan preedaran darah dalam pusat penglihatan dikorteks
serebri atau didalam retina (Cunningham F. G., 2008).
4) Otak
Pada penyakit yang belum berlanjut hanya ditemukan edema dan anemia pada
korteks serebri, pada keadaan yang berlanjut dapat ditemukan perdarahan
(Cunningham F. G., 2008).
5) Uterus
Aliran darah ke plasenta menurun dan menyebabkan gangguan pada plasenta,
sehingga terjadi gangguan pertumbuhan janin dan karena kekurangan oksigen
terjadi gawat janin. Pada preeklampsia dan eklamsia sering
peningkatan
tonus
terjadi
rahim dan kepekaan terhadap rangsangan, sehingga
terjadi partus prematur (Cunningham F. G., 2008).
6) Paru-paru
Kematian
ibu pada preeklampsia dan eklamsia biasanya disebabkan oleh
edema paru yang menimbulkan dekompensasi kordis. Bisa
juga karena
terjadinya aspirasi pneumonia, atau abses paru (Cunningham F. G., 2008).
16
Patogenesis Preeklampsia Berat
a. Vasospasme
Konsep vasospasme diajukan oleh Volhard (1918) berdasarkan
pengamatan langsung tentang pembuluh darah kecil di kuku, mata, dan
conjunctivae bulbar. Ia juga menduga dari perubahan histologis terlihat
dalam berbagai organ yang terkena.
Penyempitan pembuluh darah menyebabkan peningkatan resistensi dan
hipertensi berikutnya. Pada saat yang sama, kerusakan sel endotel
menyebabkan kebocoran yang interstisial melalui darah konstituen,
termasuk platelet dan fibrinogen, yang disimpan pada subendothelial.
Wang dan kolega (2002) juga menunjukkan gangguan protein endothel
junctional. Suzuki dan rekannya (2003) menjelaskan perubahan resistensi
ultrastruktural di wilayah subendothelial arteri pada wanita preeklampsia.
Dengan aliran darah yang berkurang karena maldistribusi, iskemia jaringan
sekitarnya akan menyebabkan nekrosis, perdarahan, dan lain organ akhir
gangguan karakteristik sindrom tersebut (Cunningham F. G., 2008).
b. Aktivasi sel endotel
Selama dua dekade terakhir, aktivasi sel endotel menjadi bintang
dalam pemahaman kontemporer dari patogenesis preeklampsia. Dalam
skema ini, faktor yang tidak diketahui - kemungkinan berasal dalam plasenta
- juga dikeluarkan ke sirkulasi ibu dan memprovokasi aktivasi dan disfungsi
vaskular endotelium. Sindrom klinis preeklampsia diperkirakan merupakan
hasil dari perubahan sel endotel yang luas.
Selain mikropartikel, Grundmann dan rekan (2008) telah melaporkan
bahwa sirkulasi sel endotel, secara signifikan meningkat empat kali lipat
dalam darah perifer wanita preeklampsia.
17
Endotelium utuh memiliki sifat antikoagulan, dan sel endotel
menumpulkan respon otot polos vaskular untuk agonis dengan melepaskan
oksida nitrat. Sel endotel yang rusak atau teraktivasi dapat memproduksi
oksida nitrat dan mengeluarkan zat yang mempromosikan koagulasi dan
meningkatkan kepekaan terhadap vasopressors (Cunningham F. G., 2008).
Pada waktu terjadi kerusakan sel endotel yang mengakibatkan
disfungsi sel endotel akan terjadi:
Gangguan metabolism prostaglandin (vasodilator kuat)
Agregasi sel trombosit untuk menutup endotel yang mengalami
kerusakan. Agregasi trombosit ini memproduksi tromboksan (TXA2),
suatu vasokonstriktor kuat. Dalam keadaan normal, kadar prostasklin
lebih tinggi daripada kadar tromboksan. Pada preeclampsia, terjadi
sebaliknya sehingga berakibat naiknya tekanan darah.
Peningkatan
endotelin
(vasopresor),
penurunan
oksida
nitrit
(vasodilator).
Peningkatan faktor koagulasi.
Bukti lebih lanjut dari aktivasi endotel termasuk perubahan
karakteristik morfologi endotel kapiler glomerulus, permeabilitas kapiler
meningkat, dan meningkatnya konsentrasi mediator yang berperan untuk
menimbulkan aktivasi endotel. Penelitian menunjukkan bahwa serum dari
wanita dengan preeklampsia merangsang sel endotel yang dikultur untuk
memproduksi prostasiklin dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan
serum wanita hamil normal (Cunningham F. G., 2008).
3.6. Diagnosis Preeklamsia
Preeklamsia secara klinis mulai tampak hanya menjelang akhir suatu
proses patofisioligis yang mungkin sudah dimuali 3 sampai 4 bulan sebelum
18
timbulnya hipertensi. Criteria minimum untuk mendiagnosis preeklamsia adalah
hipertensi dan proteinuria minimal. Semakin parah hipertensi atau proteinurianya,
semakin
pasti
diagnosis
preeklamsia.
Demikian
juga kelainan
temuan
laboratorium pada tes fungsi ginjal, hati, dan hematologis, meningkatkan
kepastian preeklamsia.
1.
Preeklamsia ringan
Diagnosis preeklamsia ringan ditegakkan berdasarkan atas timbulnya
hipertensi disertai proteinuria dan/atau edema setelah kehamilan 20 minggu.
Hipertensi : sistolik / diastolic 140/90 mmHg.
Proteinuria : 300 mg/24 jam atau 1 + dipstick
Edema : edema local tidak dimasukkan dalam criteria preeklamsia,
kecuali edema pada lengan, muka dan perut, edema generalisata.
2.
Preeklamsia berat
Preeklamsia digolongkan berat bila ditemukan satu atau lebih gejala sebagai
berikut:
Tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan darah diastolic 110 mmHg.
Tekanan darah ini tidak turun meskipun ibu hamil sudah dirawat dirumah
sakit dan sudah menjalani tirah baring.
Proteinuria 5 g/24 jam atau 4 + dalam pemeriksaan kualitatif
Oliguria, yaitu produksi urin 500 cc/24 jam
Kenaikan kadar kreatinin plasma
Gangguan visus dan serebral: gangguan kesadaran, nyeri kepala,
skotoma, dan pandangan kabur
Nyeri epigastrium atau nyeri pada kuadran kana atas abdomen (akibat
tereganggnya kapsula glisson)
19
Edema paru dan sianosis
Hemolisis mikroangiopatik
Trombositopenia berat < 100.000 sel/mm3 atau penurunan kadar alanin
dan aspartate aminotransferase
Pertumbuhan janin intrauterine yang terhambat
Sindrom HELLP
Preeklamsia berat sendiri dibagi menjadi preeklamsia tanpa impending
eclamsia dan preeklamsia berat dengan impending eclamsia bila disertai gejalagejala subjektif berupa nyeri kepala hebat, gangguan visus, muntah-muntah, nyeri
epigastrium, dan kenaikan progresif tekanan darah.
3.7 Gejala Preeklamsia
Preeklamsia mempunyai gejala-gejala sebagai berikut (Cunningham F. G.,
2008):
1) Gejala Preeklamsia
Biasanya tanda-tanda preeklamsia timbul dalam urutan: pertambahan berat
badan yang berlebihan, diikuti edema, hipertensi, dan akhirnya proteinuria. Pada
preeklamsia ringan tidak ditemukan gejala-gejala subyektif. Pada preeklamsia
berat gejala-gejalanya adalah:
a) Tekanan darah sistolik 160 mmHg
b) Tekanan darah diastolik 110 mmHg
c) Peningkatan kadar enzim hati/ ikterus
d) Trombosit < 100.000/mm
e) Oligouria < 500 ml/24 jam
f) Proteinuria > 3 g/liter
g) Nyeri epigastrium
h) Skotoma dan gangguan visus lain atau nyeri frontal yang berat
20
i) Perdarahan retina
j) Edema pulmonum
k) Koma
2) Gejala eklampsia
Pada umumnya kejang didahului oleh makin memburuknya preeklamsia
dan terjadinya gejala-gejala nyeri kepala di daerah frontal, gangguan penglihatan,
mual, nyeri di epigastrium dan hiperrefleksia. Bila keadaan ini tidak dikenali dan
tidak segera diobati, akan timbul kejang terutama pada persalinan.
3.8 Klasifikasi Preeklamsia
Pembagian preeklamsia sendiri dibagi dalam golongan ringan dan berat.
Berikut ini adalah penggolongannya (Wibowo B., Rachimhadi T., 2008):
1) Preeklamsia ringan
Dikatakan preeklamsia ringan bila :
a) Tekanan darah sistolik antara 140-160 mmHg dan tekanan darah diastolik
90-110 mmHg
b) Proteinuria minimal (< 2g/L/24 jam)
c) Tidak disertai gangguan fungsi organ
2) Preeklamsia berat
Dikatakan preeklamsia berat bila :
a) Tekanan darah sistolik > 160 mmHg atau tekanan darah diastolik > 110
mmHg
b) Proteinuria (> 5 g/L/24 jam) atau positif 3 atau 4 pada pemeriksaan
kuantitatif. Bisa disertai dengan :
1. Oliguria (urine 500 mL/24jam)
2. Keluhan serebral, gangguan penglihatan
3. Nyeri abdomen pada kuadran kanan atas atau daerah epigastrium
21
4. Gangguan fungsi hati dengan hiperbilirubinemia
5. Edema pulmonum, sianosis
6. Gangguan perkembangan intrauterine
7. Microangiopathic hemolytic anemia, trombositopenia
3) Jika terjadi tanda-tanda preeklamsia yang lebih berat dan disertai dengan
adanya kejang, maka dapat digolongkan ke dalam eklamsia
3.9 Komplikasi Preeklamsia
Nyeri epigastrium menunjukkan telah terjadinya kerusakan pada liver
dalam bentuk kemungkinan (Wibowo B., Rachimhadi T., 2008) :
1) Perdarahan subkapsular
2) Perdarahan periportal sistem dan infark liver
3) Edema parenkim liver
4) Peningkatan pengeluaran enzim liver
Tekanan darah dapat meningkat sehingga menimbulkan kegagalan dari
kemampuan sistem otonom aliran darah sistem saraf pusat (ke otak) dan
menimbulkan berbagai bentuk kelainan patologis sebagai berikut (Wibowo B.,
Rachimhadi T., 2008):
1) Edema otak karena permeabilitas kapiler bertambah
2) Iskemia yang menimbulkan infark serebal
3) Edema dan perdarahan menimbulkan nekrosis
4) Edema dan perdarahan pada batang otak dan retina
5) Dapat terjadi herniasi batang otak yang menekan pusat vital medula oblongata.
Komplikasi terberat adalah kematian ibu dan janin. Usaha utama ialah
melahirkan bayi hidup dari
ibu yang menderita preeklamsia dan eklamsia.
Komplikasi dibawah ini yang biasa terjadi pada preeklamsia berat dan eklamsia :
1) Solusio plasenta
22
Komplikasi ini terjadi pada ibu yang menderita hipertensi akut dan lebih
sering terjadi pada preeklamsia.
2) Hipofibrinogenemia
Biasanya terjadi pada preeklamsia berat. Oleh karena itu dianjurkan untuk
pemeriksaan kadar fibrinogen secara berkala.
3) Hemolisis
Penderita dengan preeklamsia berat kadang-kadang menunjukkan gejala
klinik hemolisis yang dikenal dengan ikterus. Belum diketahui dengan pasti
apakah ini merupakan kerusakkan sel hati atau destruksi sel darah merah.
Nekrosis periportal hati yang sering ditemukan pada autopsi penderita eklamsia
dapat menerangkan ikterus tersebut.
4) Perdarahan otak
Komplikasi ini merupakan penyebab utama kematian maternal penderita
eklamsia.
5) Kelainan mata
Kehilangan penglihatan untuk sementara, yang berlangsung sampai
seminggu, dapat terjadi. Perdarahan kadang-kadang terjadi pada retina. Hal ini
merupakan tanda gawat akan terjadi apopleksia serebri.
6) Edema paru-paru
Paru-paru menunjukkan berbagai tingkat edema dan perubahan karena
bronkopneumonia sebagai akibat aspirasi. Kadang-kadang ditemukan abses paruparu.
7) Nekrosis hati
Nekrosis periportal hati pada
preeklamsia/eklamsia merupakan akibat
vasospasme arteriole umum. Kelainan ini diduga khas untuk eklamsia, tetapi
23
ternyata juga dapat ditemukan pada penyakit lain. Kerusakan sel-sel hati dapat
diketahui dengan pemeriksaan faal hati, terutama penentuan enzim-enzimnya.
8) Sindroma HELLP yaitu haemolysis, elevated liver enzymes dan low platelet
Merupakan sindrom kumpulan gejala klinis berupa gangguan fungsi hati,
hepatoseluler (peningkatan enzim hati [SGPT,SGOT], gejala subjektif [cepat
lelah, mual, muntah, nyeri epigastrium]), hemolisis akibat kerusakan membran
eritrosit oleh radikal bebas asam lemakjenuh dan tak jenuh. Trombositopenia
(<150.000/cc), agregasi (adhesi trombosit di dinding vaskuler), kerusakan
tromboksan (vasokonstriktor kuat), lisosom.
9) Kelainan ginjal
Kelainan ini berupa endoteliosis glomerulus yaitu pembengkakan
sitoplasma sel endotelial tubulus ginjal tanpa kelainan struktur yang lainnya.
Kelainan lain yang dapat timbul ialah anuria sampai gagal ginjal.
10) Komplikasi lain
Lidah tergigit, trauma dan fraktur karena jatuh akibat kejang-kejang
pneumonia aspirasi dan DIC (disseminated intravascular cogulation).
11) Prematuritas, dismaturitas dan kematian janin intra-uterin.
3.10 Penatalaksanaan Preeklampsia Berat (Prasetyorini, N, 2009)
Prinsip penatalaksanaan preeklampsia adalah sebagai berikut :
1.
Melindungi ibu dari efek peningkatan tekanan darah
2.
Mencegah progresifitas penyakit menjadi eklampsia
3.
Mengatasi dan menurunkan komplikasi pada janin
4.
Terminasi kehamilan dengan cara yang paling aman
Perawatan preeklampsia berat dibagi menjadi dua unsur:
24
Pertama adalah rencana terapi pada penyulitnya: yaitu terapi medikamentosa
dengan pemberian obat-obatan untuk penyulitnya
Kedua baru menentukan rencana sikap terhadap kehamilannya: yang
tergantung pada umur kehamilannya dibagi 2, yaitu:
Ekspektatif; Konservatif : bila umur kehamilan < 37 minggu, artinya:
kehamilan dipertahankan selama mungkin sambil memberi terapi
medikamentosa
Aktif, agresif: bila umur kehamilan > 37 minggu, artinya kehamilan
diakhiri setelah mendapat terapi medikamentosa untuk stabilisasi.
Penanganan di Puskesmas
Mengingat terbatasnya fasilitas yang tersedia di Puskesmas, secara prinsip
pasien dengan PEB dan eklampsia harus dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan
dengan fasilitas yang lebih lengkap. Persiapan yang perlu dilakukan dalam
merujuk pasien PEB atau eklampsia adalah sebagai berikut :
1.
Pada pasien PEB/Eklampsia sebelum berangkat, pasang infus RD 5, berikan
SM 20 % 4 g iv pelan-pelan selama 5 menit, bila timbul kejang ulangan
berikan SM 20 % 2 g iv pelan-pelan. Bila tidak tersedia berikan injeksi
diazepam 10 mg iv secara pelan-pelan selama 2 menit, bila timbul kejang
ulangan ulangi dosis yang sama.
2.
Untuk pasien dengan eklampsia diberikan dosis rumatan setelah initial dose
di atas dengan cara : injeksi SM 40 % masing-masing 5 g im pada glutea kiri
dan kanan bergantian, atau drip diazepam 40 mg dalam 500 c RD 5 28 tetes
per menit.
3.
Pasang Oksigen dengan kanul nasal atau sungkup.
4.
Menyiapkan surat rujukan berisi riwayat penyakit dan obat-obat yang sudah
diberikan.
25
5.
Menyiapkan partus kit dan sudip lidah.
6.
Menyiapkan obat-obatan : injeksi SM 20 %, injeksi diazepam, cairan infuse,
dan tabung oksigen.
7.
Antasid untuk menetralisir asam lambung sehingga bila mendadak kejang
dapat mencegah terjadinya aspirasi isi lambung yang sangat asam.
Penanganan di rumah sakit
Dasar pengelolaan PEB terbagi menjadi dua. Pertama adalah pengelolaan
terhadap penyulit yang terjadi, kedua adalah sikap terhadap kehamilannya.
Penanganan penyulit pada PEB meliputi (Prasetyorini, 2009):
a.
Pencegahan Kejang
Tirah baring, tidur miring kiri
Infus RL atau RD5
Pemberian anti kejang MgSO4 yang terbagi menjadi dua tahap,
yaitu :
Loading / initial dose
: dosis awal
Maintenance dose
: dosis rumatan
Pasang Foley catheter untuk monitor produksi urin
Tabel 3.1 Tatacara Pemberian SM pada PEB
Loading dose
SM 20 % 4 g iv pelan-pelan
Maintenance dose
-
SM 40 % 10 g im, terbagi pada glutea kiri
dan kanan
SM 40 % 5 g per 500 cc RD5 30 tts/m
selama 5 menit
1. SM rumatan diberikan sampai 24 jam pada
perawatan konservatif dan 24 jam setelah
persalinan pada perawatan aktif
Syarat pemberian SM :
- Reflex patella harus positif
- Respiration rate > 16 x/m
- Produksi urine dalam 4 jam 100cc
- Tersedia calcium glukonas 10 %
Antidotum :
26
Bila timbul gejala intoksikasi SM dapat diberikan injeksi Calcium gluconas 10
%, iv pelan-pelan dalam waktu 3 menit
Bila refrakter terhadap SM dapat diberikan preparat berikut :
1. Sodium thiopental 100 mg iv
2. Diazepam 10 mg iv
3. Sodium amobarbital 250 mg iv
4. Phenytoin dengan dosis :
- Dosis awal 100 mg iv
- 16,7 mg/menit/1 jam
500 g oral setelah 10 jam dosis awal diberikan selama 14 jam
b. Antihipertensi
Hanya diberikan bila tensi 180/110 mmHg atau MAP 126
Bisa diberikan nifedipin 10 20 mg peroral, diulang setelah 30 menit,
maksimum 120 mg dalam 24 jam
Penurunan darah dilakukan secara bertahap :
-
Penurunan awal 25 % dari tekanan sistolik
Target selanjutnya adalah menurunkan tekanan darah < 160/105
mmHg atau MAP < 125
c.
Diuretikum
Tidak diberikan secara rutin karena menimbulkan efek :
Memperberat penurunan perfusi plasenta
Memperberat hipovolemia
Meningkatkan hemokonsentrasi
Indikasi pemberian diuretikum :
1.
Edema paru
2.
Payah jantung kongestif
3.
Edema anasarka
Krepitasi merupakan tanda edema paru. Jika terjadi edema paru, stop
pemberian cairan dan berikan diuretik misalnya furosemide 40 mg intravena.
Berdasarkan sikap terhadap kehamilan, perawatan pada pasien PEB dibedakan
menjadi perawatan konservatif dan perawatan aktif.
27
a.
Perawatan konservatif
1.Tujuan :
Mempertahankan kehamilan hingga tercapai usia kehamilan yang memnuhi
syarat janin dapat hidup di luar rahim
Meningkatkan
kesejahteraan
bayi
baru
lahir
tanpa mempengaruhi
keselamatan ibu
2. Indikasi :
Kehamilan < 37 minggu tanpa disertai tanda dan gejala impending
eklampsia
3. Pemberian anti kejang :
Seperti Tabel 3.1 di atas, tapi hanya diberikan maintainance dose (loading
dose tidak diberikan )
4. Antihipertensi
Diberikan sesuai protokol untuk PER.
5. Induksi Maturasi Paru
Diberikan injeksi glukokortikoid, dapat diberikan preparat deksametason
2 x 16 mg iv/24 jam selama 48 jam atau betametason 24 mg im/24 jam sekali
pemberian.
6. Cara perawatan :
Pengawasan tiap hari terhadap gejala impending eklampsia
Menimbang berat badan tiap hari
Mengukur protein urin pada saat MRS dan tiap 2 hari sesudahnya
Mengukur tekanan darah tiap 4 jam kecuali waktu tidur
Pemeriksaan Lab : DL, LFT, RFT, lactic acid dehydrogenase, Albumin
serum dan faktor koagulasi
28
Bila pasien telah terbebas dari kriteria PEB dan telah masuk kriteria PER,
pasien tetap dirawat selama 2 3 hari baru diperbolehkan rawat jalan.
Kunjungan rawat jalan dilakukan 1 minggu sekali setelah KRS.
7. Terminasi kehamilan
Bila pasien tidak inpartu, kehamilan dipertahankan sampai aterm
Bila penderita inpartu, persalinan dilakukan sesuai dengan indikasi
obstetrik
b. Perawatan aktif
Tujuan : Terminasi kehamilan
Indikasi :
Indikasi Ibu :
Kegagalan terapi medikamentosa :
-
Setelah 6 jam dimulainya terapi medikamaentosa terjadi kenaikan
tekanan darah persisten
Setelah 34 jam dimulainya terapi medikamentosa terjadi kenaikan
tekanan darah yang progresif
Didapatkan tanda dan gejala impending preeclampsia
Didapatkan gangguan fungsi hepar
Didapatkan gangguan fungsi ginjal
Terjadi solusio plasenta
Timbul onset persalinan atau ketuban pecah
Indikasi Janin :
Usia kehamilan 37 minggu
PJT berdasarkan pemeriksaan USG serial
NST patologis dan Skor Biofisikal Profil < 8
Terjadi oligohidramnion
29
Indikasi Laboratorium
Timbulnya HELLP syndrome
3.
Pemberian antikejang : Seperti protokol yang tercantum pada tabel 3.1
4.
Terminasi kehamilan :
Bila tidak ada indikasi obstetrik untuk persalinan perabdominam, mode of
delivery pilihan adalah pervaginam dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pasien belum inpartu
Dilakukan induksi persalinan bila skor pelvik 8. Bila skor pelvik < 8 bisa
dilakukan ripening dengan menggunakan misoprostol 25 g intravaginal tiap
6 jam. Induksi persalinan harus sudah mencapai kala II sejak dimulainya
induksi, bila tidak maka dianggap induksi persalinan gagal dan terminasi
kehamilan dilakukan dengan operasi sesar.
Indikasi operasi sesar :
- Indikasi obstetrik untuk operasi sesar
- Induksi persalinan gagal
- Terjadi maternal distress
- Terjadi fetal compromised
- Usia kehamilan < 33 minggu
2. Pasien sudah inpartu
Perjalanan persalinan dilakukan dengan mengikuti partograf
Kala II diperingan
Bila terjadi maternal distress maupun fetal compromised, persalinan
dilakukan dengan operasi sesar
Pada primigravida direkomendasikan terminasi dengan operasi sesar
30
BAB 4
PEMBAHASAN
Seorang wanita usia 34 tahun datang ke Rumah Sakit Muhammadiyah
Lamongan dengan keluhan kenceng-kenceng. Datang ke IGD RSM Lamongan
pada tanggal 28-04-2015 pukul 01:25 WIB pasien mengatakan kadang sudah
terasa kenceng-kenceng sejak 2 minggu yang lalu namun tidak teratur. Pasien
mengatakan hamil ke tiga ini HPHT 28-7-2014 dengan usia kehamilan 39-40
minggu, TP : 4-5-2015, anak pertama perempuan usia 11 tahun, lahir normal di
bidan dengan berat 2800 gram cukup bulan. Anak terahir perempuan usia 6 tahun,
lahir dengan operasi secar dengan berat 3000 gram cukup bulan. Pasien
mempunyai riwayat tekanan darah tinggi dalam kehamilan sejak kehamilan anak
pertama hingga anak ke tiga ini. Selama kehamilan pasien rutin periksa ke dokter
dan hasil pemeriksaan tekanan darah saat kehamilan ini selalu diatas 150. Pada
tanggal 23 April 2015 yang lalu pasien periksa ke dokter dan dilakukan
pemeriksaan urin dan hasilnya adalah protein urin +4.
Kemudian dari hasil urinalisis di RSM Lamongan pada tanggal 28-042015 diketahui protein urin +3 dan ke empat ekstremitas pasien mengalami edema
anasarka + sejak usia kehamilan 28 minggu. Pasien belum mengeluarkan darah
dan lendir dari jalan lahir, air ketuban juga belum pecah, pandangan pasien juga
tidak kabur, kepala tidak terasa pusing, buang air besar dan buang air kecil lancar,
tidak merasa mual dan muntah.
Pada pemeriksaan leopold di dapatkan hasil L1 TFU 34 cm, teraba bundar
lunak kesan bokong, L2 teraba punggung di sebelah kanan DJJ 151 x/menit, L3
teraba bundar keras melenting dengan goyangan belum masuk PAP, L4 5/5
31
konvergen. Dari pemeriksaan VT obstetri belum adanya pembukaan, hasil
pemeriksaan darah didapatkan hemoglobin 10,3 mg/dl, leukosit 5,2 PH 6,5,
hematokrit 32,7 dan protein urin +3.
Dimana diluar kehamilan pasien tidak pernah memiliki tekanan darah
tinggi. Dalam hal ini, pasien telah memenuhi kriteria hipertensi dalam kehamilan.
Pasien juga mengeluhkan kaki dan tangan yang sering bengkak sejak UK 28
minggu. Tekanan darah saat pasien datang adalah 158/84 mmHg. Hasil urinalisis
didapatkan proteinuria +++. Dari berbagai gejala tersebut, yakni hipertensi
>140/90, edema, dan proteinuria +++, dapat disimpulkan bahwa pasien telah
memenuhi kriteria diagnosis pre eklampsia berat.
Pada pasien ini terdapat beberapa faktor resiko yang meningkatkan
kemungkinan terkena pre eklampsia, antara lain hamil diatas usia >35 tahun,
memiliki riwayat hipertensi dalam kehamilan sebelumnya.
Terjadinya edema pada pasien ini dapat disebabkan oleh teori imunologik,
dimana terdapat maladaptasi sistem imun yang menimbulkan stress oksidatif yang
dapat
meningkatkan
permeabilitas
mikrovaskuler.
Terjadinya
proteinuria
disebabkan oleh aliran darah ke dalam ginjal menurun, sehingga menyebabkan
filtrasi glomerolus berkurang.
Pada pasien tidak didapatkan tanda-tanda impending preeklampsia
maupun komplikasi yang berat, antara lain sakit kepala (-), diplopia (-), gangguan
penglihatan (-), nyeri epigastrium (-), kejang (-), HELLP syndrome (-), gerak janin
berkurang (-).
Pasien rutin memeriksakan kehamilannya setiap bulan di bidan dan dokter
kandungan. Setiap periksa (1 bulan sekali) tekanan darah pasien selalu di atas 150,
tetapi pasien tidak pernah diberi ataupun mengkonsumsi obat antihipertensi.
32
Namun pasien rutin mengkonsumsi vitamin untuk kehamilannya (asam folat dan
tablet besi).
Terapi pada pasien ini adalah terminasi kehamilan dengan section Caesar.
Hal ini dikarenakan usia kehamilan sudah cukup bulan, yaitu 39-40 minggu, berat
badan janin cukup, usia pasien yang tua (34 tahun), usia anak terkecil 6 tahun
dilahirkan secara Caesar.
Pada pasien ini juga disarankan untuk melakukan kontrasepsi, yaitu MOW
(Metode Operasi Wanita) atau tubektomi, dimana dilakukan ligasi pada tuba
falopii. Kontrasepsi ini dilakukan untuk menghentikan kehamilan secara
permanen (sterilisasi). Hal ini dilakukan karena jumlah anak yang sudah cukup
(3), usia ibu yang sudah tua (34 tahun) dan beresiko tinggi jika hamil lagi, serta
riwayat pre eklampsia yang diderita ibu setiap mengandung.
Pada pasien diberi terapi pasca SC adalah Oksitosi Drip 20 IU/12 jam,
untuk kontraksi uterus agar mencegah perdarahan yang berlebihan (HPP). Inj
Amoxicillin untuk pencegahan infeksi sekunder. Inj Fursultiamine dan Vitamin C
untuk tambahan vitamin pada pasien. Inj Metamizole untuk mengatasi nyeri luka
operasi.
BAB 5
PENUTUP
Pre eklampsia adalah timbulnya hipertensi disertai dengan proteinuria
pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu atau segera setelah persalinan.
33
Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah 140/90 mmHg.
Proteinuria didefinisikan sebagai adanya protein dalam urin dalam jumlah 300
mg/ml dalam urin tampung 24 jam atau 30 mg/dl dari urin acak tengah yang
tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi saluran kencing. Preeklampsia ringan
adalah preeklampsia dengan TDS 140- <160 mmHg atau TDD 90-<110 mmHg
Preeklampsia disebabkan oleh multifaktor, antara lain genetik, imunologik,
iskemia plasenta, dan disfungsi endotel. Faktor resikonya antara lain,
primigravida, usia <24 tahun dan >35 tahun, obesitas, hipertensi esensial, penyakit
ginjal, kehamilan ganda, polihidramnion, diabetes, mola hidatidosa, hidrops
fetalis, sindrom antibodi antifosfolipid, riwayat preeklampsia pada kehamilan
sebelumnya dan atau pada keluarga.
Diagnosis pre eklampsia ditegakkan berdasarkan adanya dua dari tiga
gejala, yaitu penambahan berat badan yang berlebihan, edema, hipertensi, dan
proteinuria. Pemeriksaan penunjang dapat digunakan untuk menunjang diagnosis
dan mencari komplikasi, antara lain pemeriksaan darah lengkap, Urinalisis, LFT,
RFT, USG Kandungan, dan Doppler, serta NST.
Penatalaksanaan preeklampsia tergantung dari usia kehamilan dan berat
ringannya preeklampsia. Jika PER pada preterm (<37 minggu) adalah bed rest dan
pasien dapat rawat jalan. Jika PER pada aterm (>37 minggu), serviks telah
matang, dapat dilakukan terminasi kehamilan. Pada PEB berikan MgSO4 untuk
antikonvulsan setelah dipastikan syarat terpenuhi, dan terminasi kehamilan. Pada
eklampsia, persalinan harus berlangsung dalam 12 jam setelah timbulnya kejang.
34
DAFTAR PUSTAKA
Bahari. 2009. Pengaruh Persalinan dengan Komplikasi Terhadap Kemungkinan
Terjadinya Post Partum Blues di Kota Semarang. Tesis. Depok: Program
Magister FK UI.
Cunningham F. G., 2008. Hypertensive Disorders In Pregnancy. In Williams
Obstetri. 22nd Ed. New York :Medical Publishing Division, pp. 762-74
Cunningham F.G., 2010. Hipertensi dalam Kehamilan. Dalam Obstetri Williams.
Edisi 21. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC, pp. 773-819
Dharma R, dkk, 2005. Disfungsi Endotel Pada Preeklampsia. Makara Kesehatan,
9(2):63-69.
35
Hadijanto, Bantuk. 2009. Hipertensi dalam Kehamilan. Dalam: Ilmu Kebidanan.
(ed). Sarwono Prawirohardjo. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo. p 530-554
Hak, Lim. 2009. Preeclamsia. www.emedicine.medscape.com. (diakses tanggal
15 Mei 2015)
Joseph, J.M, William, S.K, Daniel,L. 2008. Beyond the Basics Preeclamsia and
Eclamsia. www.emsworld.com. (diakses tanggal 15 Mei 2015)
Magee LA, et al, 2014, Diagnosis, Evaluation, and Management of the
Hypertemsive Disorders of Pregnancy: Executive Summary, Journal
Obstetry Gynaecol 2014, 36(5):416-438.
Manuaba I. B. G., 2009. Pengantar Kuliah Obstetri. Jakarta : EGC, pp 401-31
Mochtar, R., 2010, Sinopsis Obstetri Patologi, Edisi II, Penerbit Buku Kedokteran
EGC, Jakarta
NHS, 2011, Hypertension in Pregnancy, NICE Clinical Guideline 107,
guidance.nice.org.uk/cg107
Prasetyorini, N, 2009. Penanganan Preeklampsia dan Eklampsia. Seminar POGI
Cabang Malang. Divisi Kedokteran Feto Maternal - FKUB/RSSA
Malang
Prawirohardjo, S, 2011, Ilmu Kandungan, Jakarta, PT. Bina Pustaka Sarwno
Prawirohardjo.
Prawirohardjo, S, 2011, Ilmu Kebidanan, Jakarta, PT. Bina Pustaka Sarwno
Prawirohardjo.
Sudhaberata K., 2008. Profil Penderita Preeklampsia-Eklampsia di RSU Tarakan
Kaltim.
Sunaryo R., 2008. Diagnosis dan Penatalaksanaan Preeklampsia-Eklampsia, in :
Holistic and Comprehensive Management Eclampsia. Surakarta : FK
UNS, pp 14
Surjadi, M.L. dkk, 2009. Perbandingan Rasio Ekskresi Kalsium/Kreatinin
Dalam Urin Antara Penderita Preeklamsia Dan Kehamilan Normal.
Majalah Obstetri Dan Ginekologi Indonesia, 23, 23-26.
Suyono, Y.J., 2008. Dasar-Dasar Obstetri & Ginekologi, edisi 6, Hipokrates,
Jakarta Tomasulo,
Review
P.J.
&
Lubetkin,
date),
D.,
(2009, March
Preeclamsia,
15
Availablefrom:
http://www.obgyn.health.ivillage.com/pregnancybacics/preeclamsia.cmf
Valente AM, and Economy KE, 2013, Preeclampsia, Circulation, 128:e344-e345.
Wang A, et al, 2009, Preeclampsia: The Role of Angiogenic Factors in Its
Wang
Pathogenesis, Physiology, 24:147-158.
Y, Alexander JS. Placental Pathophysiology
Pathophysiology 2008 : 261-270.
in
Preclampsia.
36
WHO, 2011, WHO Recommendations for Prevention and Treatment of
Preeclampsia
and
Eclampsia,
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_h
ealth/9789241548335/en/index.html .
Wibowo B., Rachimhadi T., 2008. Preeklampsia dan Eklampsia, dalam : Ilmu
Kebidanan. Edisi III. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo, pp. 281-99
Wibowo B., Rachimhadi T., 2008. Preeklampsia dan Eklampsia, dalam : Ilmu
Kebidanan. Edisi IV. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo, pp. 281-99
Wibowo B., Rachimhadi T., 2009. Preeklampsia dan Eklampsia, dalam : Ilmu
Kebidanan. Edisi III. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo, pp. 281-99
Wiknjosastro, H., Saifuddin, B, A., Rachimhadhi, T. 2002. Ilmu Kebidanan.
Yayasan Bina Pustaka. Jaka
Anda mungkin juga menyukai
- Fisiologi Menelan (Deglutisi)Dokumen9 halamanFisiologi Menelan (Deglutisi)Iqbal Margi SyafaatBelum ada peringkat
- Laporan Kasus - Puannita Sari S - TB NeonatusDokumen32 halamanLaporan Kasus - Puannita Sari S - TB NeonatusIqbal Margi SyafaatBelum ada peringkat
- Diare AnakDokumen30 halamanDiare AnakIqbal Margi SyafaatBelum ada peringkat
- Anatomi TenggorokDokumen18 halamanAnatomi TenggorokIqbal Margi SyafaatBelum ada peringkat
- Fisiologi BersuaraDokumen9 halamanFisiologi BersuaraIqbal Margi SyafaatBelum ada peringkat
- Ptosis Neurogenik-MiogenikDokumen27 halamanPtosis Neurogenik-MiogenikIqbal Margi SyafaatBelum ada peringkat
- Dislokasi LensaDokumen20 halamanDislokasi LensaIqbal Margi Syafaat100% (1)
- Afakia, Psedofakia Dislokasi LensaDokumen38 halamanAfakia, Psedofakia Dislokasi LensaIqbal Margi SyafaatBelum ada peringkat
- Afakia, Psedofakia, Dislokasi LensaDokumen38 halamanAfakia, Psedofakia, Dislokasi LensaIqbal Margi SyafaatBelum ada peringkat
- PTOSIS ReferatDokumen19 halamanPTOSIS ReferatIqbal Margi SyafaatBelum ada peringkat
- Skel EritisDokumen20 halamanSkel EritisIqbal Margi SyafaatBelum ada peringkat