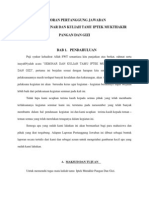Lap Dietetik
Lap Dietetik
Diunggah oleh
Friska HutahaeanHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Lap Dietetik
Lap Dietetik
Diunggah oleh
Friska HutahaeanHak Cipta:
Format Tersedia
A.
JUDUL PRAKTIKUM
GIZI BURUK
B. HARI/TGL PRAKTIKUM : RABU, 20 MARET 2013 C. PRAKTIKUM KE D. KELOMPOK KE : I (SATU) : 3 (TIGA)
E. NAMA KELOMPOK : -Feriskayanti H -Fenny Kurniawaty -Natalis Kurnianda
BAB I PENDAHULUAN & TUJUAN F. PENDAHULUAN Masalah Gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Banyak sekali yang menyebabkan masalah gizi terutama kemiskinan dan aspek pengetahuan serta perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Keadaan ini akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur harapan hidup. Secara umum, di Indonesia terdapat 2 masalah gizi yaitu masalah gizi makro dan masalah gizi mikro. Pada dasar kurang gizi makro adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan energy dan protein dan disertai dengan kekurangan zat gizi mikro. Data susenas menunjukkan bahwa Prevalensi gizi kurang, menurun dari 37,5 % menjadi 24,6 %, Namun kondisi tersebut tidak diikuti dengan penurunan prevalensi gizi buruk bahkan prevalensi gizi buruk cenderung meningkat. Oleh karena itu, pentingnya memperhatikan dengan baik masalah gizi. G. TUJUAN Untuk mengetahui tatalaksanan penanganan gizi buruk yang baik dan benar dengan member asupan makanan sesuai keadaan pasien. Untuk dapat mempraktikkan secara benar menu makanan bagi penderita gizi buruk. Untuk mengetahui secara langsung jenis-jenis makanan penderita gizi buruk.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA H. TINJAUAN PUSTAKA Gizi buruk adalah suatu keadaan patologis yang terjadi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan tubuh akan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang relatif lama (Moehji, 2002). Gizi buruk adalah suatu kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi atau nutrisinya berada dibawah standar rata-rata (Nency, 2005). Gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi, atau nutrisinya di bawah standar. Gizi buruk masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Gizi buruk banyak dialami oleh bayi dibawah lima tahun (balita). Gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi, atau nutrisinya di bawah standar rata-rata. Status gizi buruk dibagi menjadi tiga bagian, yakni gizi buruk karena kekurangan protein (disebut kwashiorkor), karena kekurangan
karbohidrat atau kalori (disebut marasmus), dan kekurangan keduaduanya. Gizi buruk ini biasanya terjadi pada anak balita (bawah lima tahun) dan ditampakkan oleh membusungnya perut (busung lapar). Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan zat gizi, atau dengan ungkapan lain status gizinya berada di bawah standar rata-rata. Zat gizi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Gizi buruk (severe malnutrition) adalah suatu istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun (Nency, 2005) Kejadian Gizi Buruk pada anak balita mengarah pada kondisi kurang gizi pada anak balita. Kondisi kurang gizi ini secara langsung dapat dipengaruhi oleh: a. Konsumsi makanan yang tidak adekuat Konsumsi makanan yang tidak adekuat mengarah pada bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak balita kurang memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang. Konsumsi makan yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakcukupan pasokan zat gizi ke dalam sel-sel tubuh (Indrawani dalam Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat FKM-UI, 2007).
Defisiensi zat gizi yang paling berat dan meluas terutama di kalangan anakanak ialah akibat kekurangan zat gizi sebagai akibat kekurangan konsumsi makanan dan hambatan mengabsorbsi zat gizi. Zat energi digunakan oleh tubuh sebagai sumber tenaga yang tersedia pada makanan yang mengandung karbohidrat, protein yang digunakan oleh tubuh sebagai pembangun yang berfungsi memperbaiki sel-sel tubuh. Kekurangan zat gizi pada anak disebabkan karena anak mendapat makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan badan anak atau adanya ketidakseimbangan antara konsumsi zat gizi dan kebutuhan gizi dari segi kuantitatif maupun kualitatif (Sjahmien, 2003). Menurut Soekirman (1999) dalam Made Amin et al. (2004) menyatakan bahwa penyebab dari tingginya prevalensi gizi kurang secara langsung adalah adanya asupan gizi yang tidak sesuai antara yang dikonsumsi dengan kebutuhan tubuh, dimana asupan gizi secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola pengasuhan terhadap anak yang diberikan oleh ibu. Hal ini senada dengan pernyataan Irawan (2004) yang menyebutkan bahwa gizi kurang dan gizi buruk adalah manifestasi karena kurangnya asupan dari protein dan energi dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi AKG dan biasanya juga terdapat kekurangan dari beberapa nutrisi lainnya. Konsumsi makanan yang tidak adekuat ini erat pula kaitannya dengan keadaan infeksi pada anak balita. Anak yang tidak cukup mendapatkan makanan maka daya tahannya akan melemah sehingga mudah diserang infeksi yang akan mengurangi nafsu makan sehingga pada akhirnya dapat menderita gizi kurang (Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat, 2001).
b. Konsumsi makanan PMT-P yang tidak adekuat Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi gizi buruk adalah dengan PMT-P. PMT-P bertujuan memulihkan keadaan gizi anak balita gizi buruk melalui pemberian makanan dengan kandungan gizi yang terukur sehingga kebutuhan gizi balita terpenuhi. Sasaran PMT-P adalah anak balita gizi buruk yang dirawat di tingkat rumah tangga (Wonatorey et al., 2006). Terpenuhinya kebutuhan gizi anak balita tergantung dari asupan zat gizi anak balita. Bagi anak balita gizi kurang ataupun gizi buruk yang mendapat PMT-P, maka asupan zat gizi anak balita yang dimaksud adalah semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak balita dalam satu hari sebelumnya, terdiri dari
makanan yang berasal dari paket PMT-P dan makanan yang diberikan sehari-hari (Wonatorey et al., 2006). Dalam penelitiannya, Made Amin et al. (2004) mengungkapkan bahwa semakin baik asupan gizi maka semakin baik status gizi anak dan ditemukan adanya hubungan yang bermakna. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Soekirman (1999) bahwa asupan gizi berpengaruh pada status gizi yang baik akan tercipta status gizi yang baik (Made Amin et al., 2004). Oleh karena itu, konsumsi makanan PMT-P yang tidak adekuat juga akan berpengaruh terhadap status gizi anak balita. c. Penyakit infeksi WHO (1976) dalam Suryono dan Supardi (2004) mengidentifikasikan faktorfaktor yang berpengaruh terhadap status gizi adalah infeksi, distribusi zat gizi pada anggota keluarga, ketersediaan pangan serta penghasilan rumah tangga. Anak-anak dengan gizi buruk daya tahannya menurun sehingga mudah terserang infeksi. Penyakit infeksi yang sering diderita oleh anak dengan gizi buruk adalah diare dan ISPA (United Nation, 1997 dalam Suryono dan Supardi, 2004). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak gizi buruk dengan gejala klinis umumnya disertai dengan penyakit infeksi seperti diare, ISPA, tuberkulosis (TB) serta penyakit infeksi lainnya (Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2007). Menurut Scrimshaw et al. (1959) dalam Supariasa (2001) menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara infeksi (bakteri, virus, dan parasit) dengan malnutrisi. Mereka menekankan interaksi yang sinergis antara malnutrisi dengan penyakit infeksi dan juga infeksi akan mempengaruhi status gizi dan mempercepat malnutrisi. Mekanisme patologisnya dapat bermacam-macam, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan, yaitu: 1) Penurunan asupan zat gizi akibat kurangnya nafsu makan, menurunnya absorpsi, dan kebiasaan mengurangi makan pada saat sakit; 2) Peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat penyakit diare, mual atau muntah dan perdarahan yang terus-menerus;
3) Meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit (human host) dan parasit yang terdapat di dalam tubuh. d. Penyakit bawaan Penyebab Gizi buruk sangat banyak dan bervariatif. Beberapa faktor bisa berdiri sendiri atau terjadi bersama-sama. Di Kabupaten Kulonprogo, Gizi Burukala Dinas Kesehatan Kulonprogo, dr.Lestaryono, Mkes. mengungkapkan bahwa cukup banyak anak gizi buruk di Kabupaten Kulonprogo yang faktor utama penyebabnya adalah penyertaan penyakit bawaan seperti hydrocephalus dan jantung bawaan dimana tingkat keberhasilan penyembuhannya relatif kecil (Judarwanto, 2008).
e. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Bayi baru lahir memerlukan kebutuhan yang sangat spesifik karena pada hari-hari pertama kehidupannya memerlukan adaptasi fisiologis dan psikologis dari lingkungan intrauterin ke lingkungan ekstrauterin. Perawatan yang dibutuhkan terutama berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi, kebersihan diri, perawatan tali pusat dan kebutuhan istirahat tidur (Sacharin, 1996 dalam Rohmah et al., 2008). Pada bayi dengan berat lahir rendah maka perlu dilakukan perawatan yang lebih ekstra terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi, karena akan berpengaruh terhadap status gizinya. Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir kurang dari 2500 gram (2,5 kilogram). Bayi BBLR prematur atau kecil untuk umur kehamilannya (Moore dalam Melfiati, Ed., 1994). Hadi (2005) menyebutkan bahwa keadaan risiko pada anak balita gizi kurang dimulai pada bayi dengan BBLR yang mempunyai risiko lebih tinggi untuk meninggal dalam lima tahun pertama kehidupan. Bayi non BBLR dengan asupan gizi kurang dari kebutuhan serta masa rentan terinfeksi kuman penyakit di awal kehidupan dapat mengakibatkan penurunan status gizi. Angka teringgi yang menunjukkan adanya penurunan status gizi anak balita lahir non BBLR di Indonesia terdapat pada kelompok umur 1824 bulan (Hadi, 2001 dalam Hadi, 2005). Semakin kecil dan semakin prematur bayi maka semakin tinggi risiko gizinya (Moore dalam Melfiati, Ed., 1994).
Faktor yang Secara Tidak Langsung Mempengaruhi Kejadian Gizi Buruk pada Anak Balita a. Karakteristik Anak Balita 1) Umur Anak balita (bawah lima tahun) atau berumur 0-59 bulan merupakan kelompok umur yang paling rentan menderita KEP karena sedang dalam masa pertumbuhan sehingga memerlukan asupan gizi yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya (Soeditama, 2004). Masa kanak-kanak 1-5 tahun merupakan masa dimana kegiatan fisik anak meningkat. Menurut Muaris (2006), pertumbuhan seorang anak pada usia balita sangat pesat sehingga memerlukan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan hal tersebut, apabila asupan gizi pada masa balita tidak tercukupi maka akan mengarah pada kondisi kenaikan berat badan yang tidak memadai sehingga anak balita menjadi BGM. Selain itu, usia balita terutama pada usia 1-3 tahun merupakan masa pertumbuhan yang cepat (growth spurt), baik fisik maupun otak sehingga memerlukan kebutuhan gizi yang paling banyak dibandingkan masa-masa berikutnya. Pada masa ini anak sering mengalami kesulitan makan, apabila kebutuhan nutrisi tidak ditangani dengan baik maka akan mudah terjadi kekurangan energi protein (Marizza, 2006).
2)
Jenis
Kelamin
Menurut Almatsier (2005), tingkat kebutuhan pada anak laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan. Begitu juga dengan kebutuhan energi, sehingga laki-laki mempunyai peluang untuk menderita KEP ysng lebih tinggi daripada perempuan apabila kebutuhan akan protein dan energinya tidak terpenuhi dengan baik. Kebutuhan yang tinggi ini disebabkan aktivitas anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan sehingga membutuhkan gizi yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Supardi (2004), yang menyatakan bahwa jumlah anak balita yang mengalami KEP maupun Non-KEP mayoritas perempuan (58,5%). Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2008), menunjukkan bahwa sebanyak 61,6% anak balita perempuan memiliki nafsu makan yang kurang sehingga mempengaruhi pola
konsumsi dan tingkat konsumsi yang akan mempengaruhi status gizi pada anak balita.
3) Jarak Kelahiran Jarak kelahiran anak yang terlalu dekat dan jumlah anak yang terlalu banyak akan mempengaruhi asupan zat gizi dalam keluarga (Supariasa et al., 2001). Keluarga dengan banyak anak apalagi yang selalu ribut akan berpengaruh pada ketenangan jiwa dan secara tidak langsung akan menurunkan nafsu makan (Soetjiningsih, 1998). Sebuah keluarga yang memiliki jarak kelahiran yang terlalu dekat dengan anak sebelumnya akan mengalami kerepotan untuk mengurusnya karena anak-anak tersebut masih belum bisa mandiri mengurus dirinya sendiri.
4) Nomor Urut Anak Dalam acara makan bersama seringkali anak-anak yang lebih kecil mendapatkan jatah yang kurang mencukupi (Apriadji, 1986). Jumlah anak yang banyak pada keluarga yang keadaan sosial ekonominya cukup akan mengakibatkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima anak. Sedangkan pada keluargha dengan keadaan sosial ekonomi yang kurang, jumlah anak yang banyak akan mengakibatkan selain kurangnya kasih sayang dan perhatian pada anak juga kebutuhan primer seperti makanan, sandang, dan perumahan pun tidak terpenuhi (Soetjiningsih, 1998). Terkait dengan kejadian kurang energi protein, nomor urut anak berhubungan dengan prioritas gizi dalam keluarga. Prioritas gizi yang salah pada keluarga menunjuk pada kondisi yang biasanya lebih memprioritaskan makanan untuk anggota keluarga yang lebih besar (sepertia ayah atau kakak tertua) dibandingkan anak balita (terutama yang berusia dibawah dua tahun) sehingga apabila makan bersama-sama maka anak balita akan kalah (Rasni, 2009).
b. Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga 1) Jumlah Anggota Keluarga
Banyaknya anggota keluarga akan mempengaruhi konsumsi pangan. Menurut Suhardjo (dalam Wahid, 2007) mengatakan bahwa hubungan sangat nyata antara besar keluarga dan kurang gizi pada masing-masing keluarga. Jumlah anggota keluarga yang semakin besar tanpa diimbangi dengan meningkatnya pendapatan akan menyebabkan pendistribusian konsumsi pangan akan semakin tidak merata. Pangan yang tersedia untuk suatu keluarga besar mungkn hanya cukup untuk mencegah timbulnya gangguan gizi pada keluarga besar. Seperti juga yang dikemukakan Berg dan Sayogyo (1986), bahwa jumlah anak yang menderita kelaparan pada keluarga besar, empat kali lebih besar dibandingkan dengan keluarga kecil. Anak-anak yang mengalami gizi kurang pada keluarga beranggota banyak, lima kali lebih besar dibandingkan dengan keluarga beranggota sedikit. Hal ini didukung oleh pendapat Apriadi (1986) bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga maka pengeluaran untuk makan besar pula dan proporsi makan setiap individu keluarga akan berkurang sehingga mereka memperoleh makanan dengan kuantitas dan kualitas yang rendah. Hasil penelitian yang dilakukan Alam (2002), juga menyatakan bahwa anak dalam keluarga kecil memiliki pola dan tingkat konsumsi makanan yang lebih baik jika dibandingkan dengan anak dalam keluarga besar.
2) Tingkat Pendidikan Ibu Ibu merupakan pendidikan pertama dalam keluarga, untuk itu ibu perlu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan ibu disamping merupakan modal utama dalam menunjang perekonomian rumah tangga juga berperan dalam pola penyusunan makanan untuk rumah tangga. Sanjur (dalam Wahid, 2002) menyatakan bahwa tingkat pendidikan formal ibu rumah tangga berhubungan positif dengan perbaikan dalam pola konsumsi pangan keluarga dan pola pemberian makanan pada bayi dan anak. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi konsumsi melalui pemilihan bahan pangan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih makanan yang lebih baik dalam jumlah dan mutunya dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah (Moehdji, 2002). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Supardi (2004), yang menyebutkan bahwa faktor pendidikan ibu yang kurang dari SMA memiliki kemungkinan 1,3 kali lebih banyak terjadinya status gizi
kurang pada anak batita dibandingkan ibu yang berpendidikan lebih dari SMA. Menurut Nency dan Arifin (dalam Wahid, 2007) dari studi yang telah dilakukan, pola pengasuhan anak berpengaruh terhadap timbulnya gizi buruk. Anak yang diasuh ibunya sendiri dengan kasih sayang, apalagi ibunya berpendidikan, mengerti soal kecukupan gizi untuk anak meskipun dalam keadaan miskin ternyata anaknya lebih baik. Unsur pendidikan perempuan berpengaruh pada kualitas pengasuhan anak.
Kurangnya pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan keluarga untuk dapat memecahkan masalah gizi keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kondisi keluarga tersebut terutama tentang pola asuh anak. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang pola asuh anak dapat menyebabkan pola asuh anak yang tidak memadai sehingga mengakibatkan anak tidak suka makan atau tidak diberikan makanan seimbang dan juga dapat memudahkan terjadinya infeksi yang berakhir dengan kondisi KEP (Soekirman, 2000). 3) Status Pekerjaan Ibu Menurut Siswono (dalam Adhawiyah, 2005) kehidupan ekonomi keluarga akan lebih baik pada keluarga dengan ibu bekerja jika dibandingkan dengan kelurga yang hanya menggantungkan kehidupan ekonomi pada kepala keluarga atau ayah. Kehidupan ekonomi keluarga yang lebih baik akan memungkinkan keluarga mampu memberikan perhatian yang layak bagi asupan gizi balita. Irawan (dalam Adhawiyah, 2005) seorang ibu bekerja adalah ibu yang tiga hari atau lebih dalam seminggu meninggalkan bayinya 4 jam/hari atau lebih dalam satu waktu. Padahal disis lain menurut Handayani (dalam Adhawiyah, 2005) seorang anak usia 0-5 tahun masih sangat tergantung dengan ibunya. Balita masih perlu bantuan dari orang tua untuk melakukan tugas pribadinya dan mereka akan belajar dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya. Ibu yang bekerja akan mengurangi kuantitas untuk menemani anaknya dirumah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2005), menyatakan bahwa anak yang memiliki ibu tidak bekerja memiliki status gizi yang lebih baik dibandingkan anak balita yang memiliki ibu yang bekerja.
4) Pendapatan Keluarga
Pendapatan keluarga adalah jumlah semua hasil perolehan yang didapat oleh anggota keluarga dalam bentuk uang sebagai hasil pekerjaannya. Menurut Sayogjo (dalam Wahid, 2007) menyatakan bahwa pendapatan keluarga meliputi penghasilan ditambah dengan hasil-hasil lain. Pendapatan keluarga mempunyai peranan penting terutama dalam memberikan efek terhadap taraf hidup mereka. Efek disini lebih berorientasi pada kesejahteraan dan kesehatan, dimana perbaikan pendapatan akan meningkatkan tingkat gizi masyarakat. Pendapatan akan menentukan daya beli terhadap pangan dan fasilitas lain (pendidikan, perumahan, kesehatan) yang dapat mempengaruhi status gizi. Adanya hubungan antara pendapatan dan status gizi telah banyak dikemukan para ahli. Pertambahan pendapatan tidak selalu membawa perbaikan pada konsumsi pangan, karena waluapun banyak pengeluaran uang untuk pangan, mungkin akan makan lebih banyak, tetapi belum tentu kualitas pangan yang dibeli lebih baik. Terdapat hubungan antara pendapatan dan keadaan status gizi (Berg dan Sayogyo, 1986). Hal itu karena tongkat pendapatan merupakan faktor yang menentukan kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Sejak lama telah disepakati bahwa pendapatan merupakan hal utama yang berpengaruh terhadap kualitas menu. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa antara pendapatan dan gizi, jelas ada hubungan yang menguntungkan. Berlaku hampir universal, peningkatan pendapatan akan berpengaruh terhadap perbaikan kesehatan dan kondisi keluarga dan selanjutnya berhubungan dengan status gizi. Namun peningkatan pendapatan atau daya beli seringkali tidak dapat mengalahkan pengaruh kebiasaan makan terhadap perbaikan gizi yang efektif (Wahid, 2007). 5) Tingkat Pengetahuan Gizi Ibu Tingkat pengetahuan gizi ibu yang baik dan dilakukan secara terus menerus dapat mengatasi kesalahpahaman yang terjadi tentang pantangan konsumsi makanan tertentu menurut adat atau kebiasaan yang merupakan tradisi turun temurun. Pantangan untuk menggunakan bahan makanan tertentu yang sudah turun temurun dapat mempengaruhi
KEP (Pudjiadi, 2001). Menurut Notoatmodjo (2003), menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan perilaku yaitu tahu, sikap, dan perilaku itu sendiri. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan. Menurut Gerungan (2004), sikap memiliki segi motivasi untuk bertindak, yaitu segi dinamis menuju ke suatu tujuan. Sikap yang tidak disertai oleh kesediaan dan kecenderungan bertindak sesuai dengan pengetahuan merupakan sikap yang berbeda dari kebiasaan tingkah laku. Dalam penelitian Sitorini (2006), menyatakan bahwa sikap responden yang baik belum tentu mendukung praktek yang baik pula. Menurut hasil penelitian oleh Nugrahani (2005), terdapat hubungan yang bermakna mengenai pengetahuan ibu tentang pola pemberian dan jenis makanan pendamping ASI dengan pola pemberian makanan pendamping ASI pada bayi. Dimana semakin tinggi pengetahuan ibu maka ibu akan memberikan makanan pendamping ASI dengan pola yang benar dan sebaliknya ibu yang mempunyai pengetahuan yang rendah maka akan memberikan makanan pendamping ASI yang salah. c. Peran keluarga Keluarga adalah kumpulan orang yang tinggal bersama pada satu tempat tinggal yang disatukan dengan ikatan perkawinan dan/ darah dan/ adopsi pada dua generasi (keluarga inti) (BKKBN Jember, 2008 dalam Rasni, 2009). Lima fungsi dasar keluarga adalah fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi asuhan kesehatan, fungsi reproduksi dan fungsi ekonomi (Friedman et al., 2003 dalam Rasni, 2009). Terkait dengan fungsi asuhan kesehatan tersebut, keluarga yang berperan baik akan dapat melakukan pemberian asupan makanan anak balita sesuai kebutuhannya, terutama orang tua khususnya ibu mempunyai andil yang besar dalam pemberian asupan makanan atau nutrisi pada anak balita (Rasni, 2009). Peran ibu dalam keluarga khususnya dalam rangka pemenuhan asupan nutrisi pada anak balita berhubungan dengan tingkat pendidikan ibu, jenis pekerjaan ibu dan
tingkat pengetahuan ibu tentang gizi. Wanita yang berpendidikan lebih rendah atau tidak berpendidikan biasanya mempunyai anak lebih banyak dibandingkan yang berpendidikan lebih tinggi. Mereka yang berpendidikan rendah umumnya tidak dapat/sulit diajak memahami dampak negatif dari mempunyai banyak anak (Khomsan dan Kusharto dalam Khomsan et al., 2004). Pendidikan yang rendah, terutama pada perempuan yang umumnya berperan di sektor domestik atau menjadi pengasuh dari anggota keluarga akan menyebabkan anak tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang, tidak mendapat ASI Eksklusif, tidak mendapat MP-ASI yang tepat serta kurang mendapat zat gizi makro dan mikro dalam kuantitas dan kualitas yang cukup (Soekirman, 2001 dalam Rasni, 2009). Selain itu, tingkat pendidikan berhubungan dengan status gizi karena dengan meningkatnya pendidikan, kemungkinan akan meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan daya beli makanan (Hartriyanti dan Triyanti dalam Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat FKM-UI, 2007). Terkait dengan pekerjaan ibu, dalam penelitian Suryono dan Supardi (2004) disebutkan bahwa pekerjaan ibu secara statistik tidak berhubungan dengan status gizi anak batita, namun pekerjaan memiliki OR 5.26 yang berarti jika ibu bekerja maka kemungkinan 5.26 kali lebih banyak pengaruhnya terhadap terjadinya gizi buruk dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Keterbatasan pengetahuan ibu tentang gizi merupakan faktor penyebab tidak langsung timbulnya masalah gizi buruk. Pengetahuan gizi ibu adalah tingkat pemahaman ibu tentang pertumbuhan anak balita, perawatan dan pemberian makan anak balita gizi buruk dan pemilihan serta pengolahan makanan anak balita gizi buruk. Dalam penelitian Wonatorey et al. (2006) disebutkan bahwa peningkatan status gizi anak balita gizi buruk kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan gizi ibu dalam pengolahan dan perawatan anak balita gizi buruk melalui konseling gizi. Peningkatan pengetahuan gizi ibu ini mempengaruhi praktek pemberian makanan Gizi Burukada anak balita terutama Gizi Burukatuhan ibu dalam memberikan intervensi PMTP yang diberikan Gizi Burukada anak balita. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Susie et al. (2002) dalam Wonatorey et al. (2006) menyatakan bahwa penanggulangan gizi buruk, menunjukkan perubahan status gizi baru bisa dilihat setelah anak yang menderita
gizi buruk mengikuti program rehabilitasi atau pemulihan selama 6 bulan mencakup aspek media, dietetik dan edukatif. d. Pola asuh Menurut Marian Zeitien (2000), pola asuh gizi adalah praktek di rumah tangga yang diwujudkan dengan tersedianya pangan dan Perawatan kesehatan serta sumber lainnya untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak. Sedangkan menurut Soekirman (2000), pola asuh adalah berupa sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal memberi makan, kebersihan, memberi kasih sayang dan sebagainya kesemuanya berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan (fisik dan mental). Menurut Satoto (1990), peranan sosial ekonomi keluarga ternyata tidak konsisten sebagai determinan pertumbuhan dan perkembangan anak, karena yang penting bukan keadaan sosial ekonomi itu sendiri, melainkan bagaimana interaksi antara ibu dan anak serta lingkungan dalam mempengaruhi pertumbuhan anak.Penolakan makan pada anak kadang juga terjadi karena taste/rasa makanan yang diberikan tidak disukai anak. Namun hal ini tidak disadari oleh para ibu karena menganggap makanan yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi anak. Hal ini terutama terjadi pada makanan yang berasal dari produk pabrik. Seharusnya sebelum makanan diberikan pada anak, setidaknya ibu mencicipi makanan tersebut untuk mengetahui taste yang paling disukai anak. Secara psikologis ibu sering kali terpengaruh oleh tekstur makanan yang berbentuk halus sehingga enggan untuk mencicipi (Pattinama, 2000).
Berdasarkan penelitian LIPI (1990), anak-anak yang selalu mendapat tanggapan, respond dan pujian dari ibunya menunjukkan keadaan gizi yang lebih baik. Anak membutuhkan sentuhan ibunya secara merasa dilindungi, Karena pada dasarnya seorang anak sangat membutuhkan kehadiran ibu yang merupakan nuansa yang sulit dapat digantikan orang lain (Utoyo, 2000). Menurut Pattinama (2000), seorang ibu yang bekerja diluar rumah mempunyai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak, baik fisik maupun psikis, terutama kebutuhan akan perawatan yang baik, rangsangan yang memadai sehingga anak memperoleh aspan gizi yang seimbang. Sebenarnya hal ini dapat
teratasi jika ibu dapat melakukan hal sederhana yang dapat menyenangkan anak, misalnya dengan meluangkan sedikit waktu bersama anak. http://alwaysnutritionist.blogspot.com/2012/02/faktor-penyebab-gizi-buruk-padabalita.html Ada beberapa cara untuk mengetahui seorang anak terkena gizi buruk (busung lapar), yaitu : 1. Dengan cara menimbang berat badan secara teratur setiap bulan. Bila perbandingan berat badan dengan umurnya dibawah 60% standar WHO-NCHS, maka dapat dikatakan anak tersebut terkena busung lapar. 2. Dengan mengukur tinggi badan dan Lingkar Lengan Atas (LILA). Bila tidak sesuai dengan standar anak normal, waspadai anak tersebut terkena busung lapar.
Tanda dan gejala dari gizi buruk tergantung dari jenis nutrisi yang mengalami defisiensi. Walaupun demikian, gejala umum dari gizi buruk adalah:
Kelelahan dan kekurangan energy Pusing Sistem kekebalan tubuh yang rendah (yang mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi)
Kulit yang kering dan bersisik Gusi bengkak dan berdarah Gigi yang membusuk Sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat Berat badan kurang Pertumbuhan yang lambat Kelemahan pada otot Perut kembung Tulang yang mudah patah Terdapat masalah pada fungsi organ tubuh
http://agathariyadi.wordpress.com/tag/gizi-buruk/
BAB III HASIL, PERHITUNGAN, & PEMBAHASAN I. HASIL J. PERHITUNGAN Pembuatan F135-FC-RF-Tempe Dibuat 400 ml untuk fase rehabilitasi Dibuat 400 ml diberi 4x dalam jangka waktu 6 jam sekali sebanyak 100 ml PROTEIN (gr) 2,5 0 0 1,4 11,0 0 0 14,9
BAHAN FC (Dancow) Minyak Goreng Gula Pasir Tepung Beras Tempe Kcl + air s/d vol
BERAT/VOL E(KAL) 10 gr 24 gr 30 gr 20gr 60 gr 0,8 gr 400 ml 400 ml 50,9 216,5 109,2 72,8 89,4 0 0 405,1
K. PEMBAHASAN Pada praktikum kali ini adalah membahas tentang pembuatan berbagai jenis makanan formula penderita gizi buruk sesuai dengan tahapan-tahapan tatalaksanan gizi buruk. Gizi buruk adalah gangguan gizi akut dan berat. Gizi buruk secara klinis dapat dilihat biasanya mengalami keadaan sangat kurus, lemak otot tipis dan habis. Sedangkan pada gizi buruk secara antropometri memiliki BB/PB < -3 SD, atau BB/PB < 70 % Median atau LILA < 11,0 cm (skrinning). Adapun pada praktikum ini, kelompok 3 membuat formula untuk fase rehabilitasi yaitu F!#%-FC-RC-TEMPE yang merupakan diit dianjurkan WHO-Depkes-RI. Dari hasil praktikum, Pembuatan formula sudah sesuai dengan baik, pada formula untuk fase rehabilitasi ini merupakan makanan cair kental, ini diberikan 4x dalam sehari dengan volume 100 ml setiap pemberian. Pada fase ini, sangat penting bagi pasien karena merupakan tahapan pemberian makanan tumbuh kejar agar BB dapat naik terus-menerus namun secara perlahan. Jika dilihat dari semua jenis makanan pada tiap fase seperti F75 F135 ini, Semakin tinggi formula makanan , maka semakin tinggi pula konsistensinya. Yang mana, pada fase stabilisasi diberikan F75 yang konsistensinya cair dan harus diberikan perlahan melalui parenteral. Sedangkan fase transisi diberikan F100 yang mana konsisstensinya tidak terlalu cair, dan diberikan 12 x selama 2 jam, Jika sudah membaik dapat ditingkatkan 3 jam sekali. Sedangkan seperti Resomal, bias diberikan 50 ml dalam sekali masuk untuk pasien gizi buruk, namu perlu diperhatikan ada atau tidak adanya edema. Jika ad pemberian dapat dikurangi, yang terpenting dalam penanganan gizi buruk adalah pemberian cairan dan frekuensi makanan pada anaknya. Jika anak gemuk, maka perlu diperhatikan dan diberikan asupan rendah lemak dan rendah laktosa. Pada pembuatan F135 modifikasi ini dilakukan dengan mempersiapkan bahanbahan dan alat-alat. Pertama-tama tempe di blender dengan air kemudian disaring dengan air secukupnya. Setelah itu, aduk susu dan tepung beras dengan air hangat secukupnya, setelah itu, agar minyak yang digunakan tidak timbul keatas maka gula pasir diaduk
terlebih dahulu dengan minyak kemudian dicampur pada larutan susu dan tepung beras, setelah itu campurkan semua bahan kedalam panic yaitu sari tempe, larutan campuran susu, tepung, gula, minyak kemudian larutan kcl. Setelah itu dimasak diatas api selama 57 menit hingga mendidih dan agak kental. Jumlah larutan keseluruhan harus mencapai vol 400 ml, untuk mencukupi kebutuhan anak gizi buruk dalam satu hari . karna kcl tidak ad waktu praktikum kemarin, maka kcl diganti dengan garam. Yang terpenting dalam praktikum ini adalah bagaimana membuat pasien gizi buruk dapat sembuh, dapat tersenyum dan kembali normal. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN L. KESIMPULAN
Dalam praktikum ini, yang terpenting dapat melakukan tahapan-tahapan penatalaksanaan gizi buruk dengan benar, dari fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan fase tindak lanjut. Dalam fase-fase ini diberikan asupan makanan yang sesuai dengan kondisi pasien, dan perlu diperhatikan cairan dan frekuensi makanan dalam setiap fase. M. SARAN Perlu diperhatikan frekuensi makanan pasien, pemberian, dan bentuk makanan. Modifikasi makanan dapat dilakukan yang terpenting sesuai dengan kondisi pasien. Untuk resomal bias diberikan 50 cc setiap pemberian, namun perlu diperhatikan jika ada edema. Pemberian formula yang berbentuk cair dapat diberikan perlahan-lahan agar pasien tidak tersedak dan muntah.
A. JUDUL PRAKTIKUM
: OBESITAS PADA DEWASA
B. HARI/TGL PRAKTIKUM : RABU, 01 MEI 2013 C. PRAKTIKUM KE D. KELOMPOK KE E. NAMA KELOMPOK : II (DUA) : 3 (TIGA) : -Feriskayanti H -Fenny Kurniawaty -Natalis Kurnianda
BAB I PENDAHULUAN & TUJUAN F. PENDAHULUAN Dewasa ini masalah kegemukan (obesitas) merupakan masalah global yang melanda masyarakat dunia baik di Negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Perubahan gaya hidup termasuk kecenderungan mengkonsumsi makanan yang
mengandung lemak tinggi maerupakan factor yang mendukung terjadinya kelebihan berat badan(overweight) dan obesitas. Masalah Gizi tidak lebih hanya menyebabkan kegemukan dan obesitas tetapi juga memicu penyakit lain misalnya hipertensi , penyakit jantung, diabetes mellitus dan lain-lain. Komplikasi antara obesitas dengan penyakitpenyakit tersebut dapat menyebabkan kematian.. G. TUJUAN Untuk dapat mengetahui definisi obesitas , factor penyebab , gejala, dampak serta cara mengatasi dan mencegah obesitas. Untuk dapat menurunkan berat badan pasien secara bertahap. Untuk menangani dan memberikan penanganan atau pelayanan kesehatan terhadap penyakit obesitas. Untuk dapat memberikan diet yang benar pada orang yang overweight, ataupun yang obesitas. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
H. TINJAUAN PUSTAKA Obesitas (obesity) berasal dari bahasa latin yaitu ob yang berarti akibat dan esum artinya makan. Sehinggga obesitas dapat didefinisikan sebagai akibat dari pola makan yang berlebihan. WHO membuat defininsi baku dari obesitaas dan menyatakan kondisi ini sebagai suatu keadaan dimana terjadi penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Secara umum kegemukan adalah kelebihan lemak tubuh yang dialami oleh seseorang secara kronis. Pada kondisi normal, lemak tubuh berfungsi sebagai cadangan energi, pengatur suhu tubuh, pelindung dari trauma, dan fungsi-fungsi lainnnya. Namun bila lemak ditubuh tersebut berlebih, akan disimpan didalam tubuh sebagai cadangan lemak inilah yang menimbulkan kegemukan. Secara ideal, pada tubuh seorang perempuan terdiri dari 25-30% lemak, sedangkan laki-laki 18-23%. Apabila lemak dalam tubuh lebih, maka sudah dikategorikan gemuk. Cara menghitung kegemukan yang paling mudah adalah dengan membandingkan antara berat badan (kg) dengan tinggi badan (m) yang dikenal dengan istilah Body Mass Index (BMI) atau indeks masa tubuh. Berdasarkan klasifikasi WHO pada tahun 1998, dinyatakan BBL bila IMT 25,0 29,9 kg/m2 dan obesitas bila IMT 30,0 kg/m2. Hal ini lebih dirinci sebagai berikut: 1. 2. 3. Obesitas ringan IMT 30,034,9 Obesitas sedang IMT 35,039,9 Obesitas berat (morbid) IMT 40,0 kg/m2
Kegemukan tidak terjadi secara instans, tetapi pelahan-lahan berdasarkan jumlah cadangan lemak yang terus bertambah karena cadangan lemak tersebut tidak digunakan untuk beraktifitas. Dengan demikian tidak ada pembakaran kalori dan cadangan lemak akan terus bertambah seiring bertambahnya lemak didalam tubuh. Pada awalnya, sering tidak disadari bahwa gaya hidup sesserang terutama pola makanlah yang paling memicu terjadinya kegemukan. Tubuh seseorang memerlukan kalori sebagai penggerak aktifitaas sehari-hari. Kalori tersebut didapatkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Ketika konsumsi kalori tersebut seimbang dengan yang sdibutuhkan oleh tubuh, maka tidak akan jadi masalah. Namunn sebaliknya, jika seseiorang mengonsumsi makanan atau minuman dengan jumlah kalori yang lebih besar dari yang dibutuhkan,
kalori tersebut akan disimpan dalam tuuh sebagai cadangan energy. Bagi mereka yang suka makanan bekalori tinggi seperti fast food, coklat, es krim, dan lain sebagainya sebaiknya bisa menyeimbangkan dengan menyalurkann energi yang masuk kedalam tubuh tersebut. Cara yang paling gampang adalah dengan berolahraga.
http://qoryasyah.blogspot.com/2012/07/makalah-obesitas-dan-perawatnya.html Berdasarkan hukum termodinamik, obesitas disebabkan adanya keseimbangan energi positif, sebagai akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi, sehingga terjadi kelebihan energi yang disimpan dalam bentuk jaringan lemak.Sebagian besar gangguan keseimbangan energi ini disebabkan oleh faktor eksogen/nutrisional (obesitas primer) sedang faktor endogen (obesitas sekunder) akibat kelainan hormonal, sindrom atau defekgenetik hanya sekitar 10%. Penyebab obesitas belum diketahui secara pasti. Obesitas adalah suatu penyakit multifaktorial yang diduga bahwa sebagian besar obesitas disebabkan oleh karena interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan, antara lain aktifitas, gaya hidup, sosial ekonomi dan nutrisional yaitu perilaku makan dan pemberian makanan padat terlalu dini pada bayi.3,4
Parental fatness merupakan faktor genetik yang berperanan besar. Bila kedua orang tua obesitas, 80% anaknya menjadi obesitas; bila salah satu orang tua obesitas, kejadian obesitas menjadi 40% dan bila kedua orang tua tidak obesitas, prevalensi menjadi 14%. Hipotesis Barker menyatakan bahwa perubahan lingkungan nutrisi intrauterin menyebabkan gangguan perkembangan organ-organ tubuh terutama kerentanan terhadap pemrograman janin yang dikemudian hari bersama-sama dengan pengaruh diet dan stress lingkungan merupakan predisposisi timbulnya berbagai penyakit dikemudian hari. Mekanisme kerentanan genetik terhadap obesitas melalui efek pada resting metabolic rate,thermogenesis non exercise, kecepatan oksidasi lipid dan kontrol nafsu makan yang jelek.Dengan demikian kerentanan terhadap obesitas ditentukan secara genetik sedang lingkungan menentukan ekspresi fenotipe.
Aktifitas fisik. Aktifitas fisik merupakan komponen utama dari energy expenditure, yaitu sekitar 20-50% dari total energy expenditure. Penelitian di negara maju mendapatkan hubungan antara aktifitas fisik yang rendah dengan kejadian obesitas. Individu dengan aktivitas fisik yang rendah mempunyai risiko peningkatan berat badan sebesar = 5 kg.Penelitian di
Jepang menunjukkan risiko obesitas yang rendah (OR:0,48) pada kelompok yang mempunyai kebiasaan olah raga, sedang penelitian di Amerika menunjukkan penurunan berat badan dengan jogging (OR: 0,57), aerobik (OR: 0,59), tetapi untuk olah raga tim dan tenis tidak menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan. Penelitian terhadap anak Amerika dengan tingkat sosial ekonomi yang sama menunjukkan bahwa mereka yang nonton TV = 5 jam perhari mempunyai risiko obesitas sebesar 5,3 kali lebih besar dibanding mereka yang nonton TV = 2 jam setiap harinya.10 Faktor nutrisional. Peranan faktor nutrisi dimulai sejak dalam kandungan dimana jumlah lemak tubuh dan pertumbuhan bayi dipengaruhi berat badan ibu. Kenaikan berat badan dan lemak anak dipengaruhi oleh : waktu pertama kali mendapat makanan padat, asupan tinggi kalori dari karbohidrat dan lemak5 serta kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung energi tinggi. Penelitian di Amerika dan Finlandia menunjukkan bahwa kelompok dengan asupan tinggi lemak mempunyai risiko peningkatan berat badan lebih besar dibanding kelompok dengan asupan rendah lemak dengan OR 1.7. Penelitian lain menunjukkan peningkatan konsumsi daging akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 1,46 kali.Keadaan ini disebabkan karena makanan berlemak mempunyai energy density lebih besar dan lebih tidak mengenyangkan serta mempunyai efek termogenesis yang lebih kecil dibandingkan makanan yang banyak mengandung protein dan karbohidrat. Makanan berlemak juga mempunyai rasa yang lezat sehingga akan meningkatkan selera makan yang akhirnya terjadi konsumsi yang berlebihan. Selain itu kapasitas penyimpanan makronutrien juga menentukan keseimbangan energi. Protein mempunyai kapasitas penyimpanan sebagai protein tubuh dalam jumlah terbatas dan metabolisme asam amino di regulasi dengan ketat, sehingga bila intake protein berlebihan dapat dipastikan akan di oksidasi; sedang karbohidrat mempunyai kapasitas penyimpanan dalam bentuk glikogen hanya dalam jumlah kecil. Asupan dan oksidasi karbohidrat di regulasi sangat ketat dan cepat, sehingga perubahan oksidasi karbohidrat mengakibatkan perubahan asupan karbohidrat. Bila cadangan lemak tubuh rendah dan asupan karbohidrat berlebihan, maka kelebihan energi dari karbohidrat sekitar 60-80% disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Lemak mempunyai kapasitas penyimpanan yang tidak terbatas. Kelebihan asupan lemak tidak diiringi peningkatan oksidasi lemak sehingga sekitar 96% lemak akan disimpan dalam jaringan lemak. Faktor sosial ekonomi. Perubahan pengetahuan, sikap, perilaku dan gaya hidup, pola makan, serta peningkatanpendapatan mempengaruhi pemilihan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi.Suatu data menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir terlihat adanya perubahan gayahidup yang menjurus pada penurunan aktifitas fisik, seperti: ke sekolah dengan naikkendaraan dan kurangnya aktifitas bermain dengan teman serta lingkungan rumah yangtidak memungkinkan anak-anak bermain diluar rumah, sehingga anak lebih
senangbermain komputer / games, nonton TV atau video dibanding melakukan aktifitas fisik.Selain itu juga ketersediaan dan harga dari junk food yang mudah terjangkau akanberisiko menimbulkan obesitas. http://yanhaluciyan.blogspot.com/2010/01/bab-i-pendahuluan-1.html
Penimbunan lemak yang berlebihan dibawah diafragma dan di dalam dinding dada bisa menekan paru-paru, sehingga timbul gangguan pernapasan dan sesak napas, meskipun penderita hanya melakukan aktivitas yang ringan. Gangguan pernapasan bisa terjadi pada saat tidur dan menyebabkan terhentinya pernapasan untuk sementara waktu (tidur apneu), sehingga pada siang hari penderita sering merasa ngantuk. Obesitas bisa menyebabkan berbagai masalah ortopedik, termasuk nyeri punggung bawah dan memperburuk osteoartritis (terutama di daerah pinggul, lutut dan pergelangan kaki). Juga kadang sering ditemukan kelainan kulit. Seseorang yang menderita obesitas memiliki permukaan tubuh yang relatif lebih sempit dibandingkan dengan berat badannya, sehingga panas tubuh tidak dapat dibuang secara efisien dan mengeluarkan keringat yang lebih banyak Surasmo, R., Taufan H. Penanganan obesitas dahulu, sekarang dan masa depan. Dalam Naskah Lengkap National Obesity Symposium I, Editor: Tjokroprawiro A., dkk. Surabaya, 2002; 53 65 BAB III HASIL, PERHITUNGAN, & PEMBAHASAN I. HASIL J. PERHITUNGAN Diketahui : Seorang gadis bernama Nn. A berumur 23 tahun merupakan seorang mahasiswi pada salah satu perguruan tinggi dikotanya, sudah beberapa bulan ini merasa cepat lelah dan sering sulit bernapas bila berjalan jauh atau tidak melakukan aktifitas yang agak berat . Nn.A tinggal bersama orangtuanya dan merupakan anak satu-satunya .
Ayahnya seorang pengusaha perkayuan dan ibunya seorang pegawai negeri sipil . Ia jarang berolahraga dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler dikampusnya, Sepulang dari kampus biasanya ia bersantai dikamarnya sambil mendengarkan musik atau mengerjakan tugas. Nn A senang sekali makan-makanan cemilan, Pola makannya 3x sehari makan-makanan lengkap diselingi makanan cemilan diantara waktu-waktu istirahat. Pada malam hari sambil menonton Tv , ia makanmakanan yang tinggi kalori untuk menghilangkan kejenuhan Nn.A menyukai makanmakanan berlemak atau bersantan. Makanan fastfood, coklat dan kue-kue , tetapi kurang menyukai sayuran. Dokter keluarga menasehatinya untuk menurunkan berat badan untuk mengurangi resiko yang serius yaitu jantung koroner. Oleh karena itu, dianjurkanuntuk mengunjungi ahli gizi untuk terapi gizinya. Sebagai ahli gizi , berikan pelayanan asuhan Gizi berdasarkan NCP pada Nn dan susun menu sehari. Jawaban : ANTROPOMETRI : Umur 23 tahun, BB 80 Kg, TB 150 cm IMT = BB/TB = 80 /(1,5)2 = 40/2,25 = 35,56 -> OBESITAS BBI = (TB-100) x 90% = (150-100) x 90% = 45 Kg BEE = 655 + (9,6 X BB) + (1,7 X TB) (4,7 X U) = 655 + (9,6 X 80) + (1,7 X 150) (4,7 X 23) = 1569,9 kkal TEE = BEE x FA = 1569,9 x 1,3 = 2040,87 kkal 500 kkal = 1540,87 kkal Protein = 16 % x 1540,87 kkal / 4 = 61,6348 gr. Lemak = 25 % x 1540,87 / 9 = 42,80 gr Karbohidrat = 59 % x 1540,87 / 4 = 227,2 gr
K. PEMBAHASAN Pada praktikum ini kami membuat menu sehari tentang obesitas Nn.A , yang mana memiliki IMT lebih dari normal dan resiko serius jantung koroner. Dokter keluarga sendiri menyarankan Nn.A untuk menurunkan beratbadan karena sudah terlalu kegemukan , Nn. A ini sangat sulit menurunkan berat badan karena pola makan nya tidak benar, serta senang sekali makan-makanan cemilan, makanan yang berlemak, bersantan, makanan fastfood, cokelat, dan kue-kue. Selain itu juga Nn. A ini sangat jarang sekali berolahraga dan kurang aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler sehingga sulit untuk bernafas bila berjalan jauh. Untuk itu, pada kasus ini saya membuat jenis die dengan prinsip diet rendah energi yang mana dimaksudkan dapat mengurangi energy yang masuk sebanyak 500 kkal / hari, selain itu pentingnya memberikan tips-tips makanan sehat yang baik untuk dikonsumsi dan teknik pengolahan juga perlu . Dalam mengurangi berat badan ini dapat memberikan makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan dan sayuran. Supaya Nn.A dapat mencapai berat badan yang diinginkan ataupun ingin menurunkan beratbadan , Nn.A dapat menerapkan pola hidup sehat dengan makanan seimbang yang disertai olahraga yang cukup dan juga pentingnya menjadwalkan menu sehari agar lebih teratur untuk makanan nya dapat lbih divariasikan agar lebih menarik dengan porsi yang cukup. Adapun disini, saya membuat menu untuk Nn.A adalah o Makan pagi diberikan sandwich o Snack pagi diberikan salad buah o Makan siang diberikan nasi merah dan dadar jamur tempe serta tumisan sayuran o Snack sore diberikan juice tomat o Makan malam diberikan bihun goreng + tempe goreng Dari menu yang saya buat sudah cukup bervariasi begitu juga dengan porsinya sudah cukup. Namun perlu diperhatikan tekhnik pengolahannya, cenderung kering dan berminyak / digoreng padahal di syarat diit dan bahan
makanan tidak dianjurkan makanan berlemak dan digoreng, untuk itu perlu ditinjau kembali membuat syarat diit, tujuan diit, prinsip diit, dan bahan makanan tidak dianjurkan dalam pembuatan menu satu hari untuk mncukupi kebutuhan pasien. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN L. KESIMPULAN Dalam praktikum ini yang terpenting mengerti bagaimana cara menangani kasus obesitas seperti Nn.A serta mengerti bagaimana menyusun menu yang sehat dan memenuhi kebutuhan Nn.A. Adapun yang perlu iperhatikan tekhnik pengolahan menu harus disesuaikan dengan kasus M. SARAN o Pentingnya memperhatikan pemberian intervensi , monev, materi edukasi, serta perhitungannya. o Memperhatikan daftar masalah-masalah yang ada dalam kasus untuk dibahas dan ditangani.
A. JUDUL B. HARI / TANGGAL C. PERTEMUAN KE D. NAMA KELOMPOK
: STANDAR MAKANAN UMUM RUMAH SAKIT : Rabu, 25 juni 2013 : V (LIMA) : Feriskayanti H Fenny Kurniawati M Natalis Kurnianda
BAB I PENDAHULUAN & TUJUAN E. PENDAHULUAN Standar makanan rumah sakit merupakan pedoman pemberian makanan bagi pasien rumah sakit yang mana, sangat penting diperhatikan bentuk olahan, penyediaan, penyajian, pemberian, dan diperhatikan serta disesuaikan kondisi pasien. Makanan merupakan suatu hal yang sangat pentingdidalam kehidupan manusia, dimana makanan berfungsi memberikan tenaga atau energy panas pada tubuh, membangun jaringanjaringan tubuh yang baru pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit serta sebagai sumber bahan pengganti sel-sel tua yang using dimakan usia. Untuk mendapatkan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, maka perlu diadakan pengawasan terhadap hygiene dan sanitasi makanan dan minuman terutama usaha untuk di rumah sakit. F. TUJUAN Agar mahasiswa mampu membuat makanan sesuai standar makanan di rumah sakit Agar mahasiswa mengerti bagaimana cara membuat/ menyebabkan serta menyajikan dengan benar standar makanan di rumah sakit Membina mahasiswa terampil dalam bidang pembuatan makanan yang bergizi yang mana disesuaikan dengan standar makanan rumah sakit. BAB II TINJAUAN PUSTAKA G. TINJAUAN PUSTAKA
Standar Makanan Rumah Sakit A. Makanan Biasa Makanan biasa diberikan kepada penderita yang tidak memerlukan makanan khusus berhubung dengan penyakitnya. Susunan makanan sama dengan makanan orang sehat, hanya tidak diperbolehkan makanan yang merangsang atau yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Makanan ini cukup kalori, protein dan zat zat gizi lain.
B.
Makanan Lunak Makanan lunak diberikan kepada penderita sesudah operasi tertentu dan pada penyakit infeksi dengan kenaikan suhu badan tidak terlalu tinggi. Menurut keadaan penyakit, makanan lunak dapat diberikan langsung kepada penderita atau
C.
Makanan saring Makanan saring diberikan kepada penderita sesudah mengalami operasi tertentu, pada infeksi akut,termasuk infeksi saluran pencernaan seperti gastro enteritis dan pada kesukaran menelan. Menurut keadan penyakit, makanan saring dapat diberikan langsung kepada penderita atau merupakan perpindahan dari makanan cair ke makanan lunak.
D.
Makanan cair Makanan cair diberiakn kepada penderita sebelum dan sesudah operasi tertentu, dalam keadaan mual dan muntah, dalam keadaan menurun, dengan suhu badan sangat tinggi atau infeksi akut. Makanan ini diberikan berupa cairan jernih yang tidak merangsang dan tidak meninggalkan sisa. Nilai gizi sangat rendah sehingga pemberiannya dibatasi selama 1-2 hari saja. Makanan dan minuman yang boleh diberikan : teh,kopi,kaldu jernih,air bubur kacang hijau,sari buah,sirop dan gula pasir.
E.
Makanan lewat pipa Makanan lewat pipa diberikan kepada penderita yang tidak dapat makan melalui mulut oleh karena gangguan jiwa, prekoma, anorexia nervosa, kelumpuhan otot-otot menelan, atau sesudah operasi mulut, tenggorokan dan saluran pencernaan. Makanan diberikan berupa sari buah dan cairan kental yang dibut dari
susu, telur, gula dan margarin. Cairan hendaknya dapat dimasukkan melalui pipa karet hidung,lambung atau rectum. Pemakaian gula pasir dan susu penuh (whole) disesuaikan dengan kemampuan penderiat untuk menerimanya. Bila terjadi kembung perut atau diare. Pemakaian gula pasir dikurangi dan susu penuh diganti dengan susu skim atau susu rendah laktosa. Karena kurang dalam besi dan vitamin, kedalam makanan dimasukkan 8 mg preparat ferrosulfat 3 tablet vitamin B kompleks dan 150 mg preparat vitamin C. Makanan dapat dibuat sekaligus untuk 24 jam, dimasukkan kedalam botolbotol steril dan disimpan di lemari es. Sebelum diberikan, makanan dipanaskan hingga suhu badan. Banyaknya makanan sehari adalah 1500-2000 ml yang dibagi dalam 4 porsi. Menurut kebutuhan penderita, dapat diberikan salah satu dari 3 macam makanan lewat pipa (MLP). 1. 2. 3. Makanan lewat pipa I (MLP I) Kalori : 1500 Makanan lewat pipa II (MLP II) Kalori : 1700 Makanan lewat pipa III (MLP III) Kalori : 2200
file://localhost/C:/Users/user/Documents/standar%20makanan%20rumah%20sakit %20%20%20Nita's%20Blog.htm BAB III PERHITUNGAN & PEMBAHASAN H. PERHITUNGAN Takaran per sajian 27 gr = Energi 130 kkal Dalam 100 gr = 100 x 130 : 27 = 481,48 kkal 100 gr / 481,48 kkal = x / 1500 kkal X = 150000 / 481,48 kkal X = 311, 53 gr.
Protein dalam 27 gr = 7 gr Berarti dalam 311,53 gr = ? 311,53 gr x 7 = 27 gr x a a = 2180,71 /27 = 80,76 gr
% protein = 80,76 x 4 x 100 % / 1500 = 21,536 % I. PEMBAHASAN :
Standar makanan rumah sakit merupakan pedoman pemberian makanan baggi pasien di rumah sakit. Ada 2 golongan yaitu makanan biasa dan makanan khusus.. makanan biasa sama dengan makanan sehari-hari yang beraneka ragam, bervariasi dengan bentuk, tekstur dan aroma yang normal. Susunan makanan mengacu pada pola menu seimbang dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi orang dewasa sehat. Makanna biasa diberikan kepada pasien yang berdasarkan penyakit tidak memerlukan makanan khusus (diet). Walau tidak ada pantangan secara khusus, makanan sebaiknya diberikan dalam bentuk yang mudah dicerna dan tidak merangsang pada saluran cerna. Makanan biasa merupakan makanan dasar untuk modifikasi makanan khusus. Dapat memenuhi kebutuhan gizi pasien. Contohnya seperti nasi putih, tempe goreng, sayur asam dll. Makanan khusus adalah perubahan konsentrasi: makanan lunak, makanan saring, makanan cair, diet serat rendah & tinggi. Penambahan atau pengurangan energy: diet kalori rendah & tinggi, penambahan atau penguranagn jenis makanan : diet garam rendah, diet laktosa rendah, diet albumin tinggi. Perubahan komposisi zat gizi : diet diabetes mellitus, diet ketogenic, diet jantung, diet hati. Perubahan jumlah dan frekuensi makanan : diet lambung, penghilangan atau pantangan makanan spesifik : diet alergi. Makanan lunak adalah makanan yang memiliki tekstur yang mudah dikunyah, ditelan dan dicerna dibandingkan makanan biasa. Makanan ini mengandung cukup zat-zat gizi, asalkan pasien mampu mengkonsumsi makanan dalam jumlah cukup. Menurut keadaan penyakit makanan lunak dapat diebrikan langsung kepada pasien atau sebagai perpindahan dari makanan saring ke makanan biasa. Makanan saring adalah makanan semipadat yang mempunyai tekstur lebih halus daripada makanan lunak, sehingga lebih mudah dicerna dan ditelan. Menurut keadaan penyakit, makanan saring dapat diberikan langsusng kepada pasien atau merupakan perpindahan dari makanan cair kental ke makanan lunak. Makanan cair adalah makanan yang mempunyai konsistensi cair hingga kental. Makanan ini diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan mengunyah, menelan dan
mencernakan makanan yang disebabkan oleh menurunnya kesadaran, suhu tinggi, rasa mual, muntah, pasca pendarahan saluran cerna, serta pra dan pasca bedah. Makanan dapat diberikan secara oral ataupun parental. Makanan cair jernih adalah makanan yang disajikan dalam bentuk cairan jernih pada suhu ruang dengan kandungan sisa (residu)minimal dan tembus pandang bila diletakkan dalam wadah bening. Jenis carian yang diebrikan tergantung pada keadaan penyakit atau jenis operasi yang dijalankan. Makanan cair penuh adalah makanan yang berbentuk car atau semi cair pada suhu ruang dengan kandungan serat minimal & tidak tembus pandang bila diletakkan dalam wadah bening. Jenis makanan yang diberikan tergantung pada keadaan pasien. Makanan ini langsung dapat diberikan kepada pasien atau sebagai perpindahan dari makanan cair jernih ke makanan cair kental. Makanan cair kental adalah makanan yang mempunyai konsistensi kental atau semi padat pada suhu kamar, yang tidak membutuhkan proses mengunyah dan mudah ditelan. Menururt keadaan penyakit, makanan cair kental dapat diberikan langsung kepada pasien atau merupakan perpindahan dari makanan cair penuh ke makanan saring. Pada praktek kali ini kelompok kami mendapatkan menu makanan cair penuh dengan konsentrasi biasanya, konsentrasi berupa produk. Adapun yang kami buat adalah dari produk minuman dancow, dengan perhitungan zat gizi dalam 100gr adalah :481,48 kkal, dan jika dalam volume 2000 ml, energy 1500 kkal , maka susu dancow yang disajikan sebanyak 311,53 gram. Dan persen protein mencapai 21, 536 %. Pada produk untuk makanan cair penuh dari pabrikan ini sebenarnya kurang baik, karena jika hanya dari susu saja, terutama yang mengandung protein lebih maka akan membuat gangguan hormone dan gangguan ginjal, sebaiknya disertai dengan asupan gizi seimbang. Dan yang terpenting yang harus diingat adalah pasien yang mengonsumsi zat gizi dengan konsistensi tinggi boleh diberikan asupan dengan konsistensi rendah, namun tidak untuk sebaliknya. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN J. KESIMPULAN
Standar makanan rumah sakit merupakan pedoman pemberian makanan bagi pasien di rumah sakit. Adapun makanan terdiri dari beberapa golongan yaitu : Makanan biasa, Makanan lunak, Makanan Saring, Makanan Cair. K. SARAN Perlu diperhatikan pasien untuk pemberian makanan Perlu diperhatikan bentuk makanan, pengolahan dan cara pemberian.
A. JUDUL PRAKTIKUM
: STUDY KASUS COLITIS
B. HARI/TGL PRAKTIKUM : RABU, 04 Juli 2013 C. PRAKTIKUM KE D. KELOMPOK KE E. NAMA KELOMPOK : VI (ENAM) : 3 (TIGA) : -Feriskayanti H -Fenny Kurniawaty -Natalis Kurnianda
BAB I PENDAHULUAN & TUJUAN F. PENDAHULUAN Kolitis ulserativa adalah peradangan akut atau kronik pada kolon (usus besar). Karena peradangan itu, terjadi kram perut, demam, dan diare berdarah. Peradangan itu dimulai di rektum atau kolon sigmoid (ujung bawah dari usus besar) dan kemudian menyebar ke sebagian atau seluruh bagian usus besar. Pada bagian yang meradang akan terjadi pembengkakan. Kolitis di derita oleh siapa pun dan pada umur berapa pun. Tapi biasanya mulai diderita pada umur 15-30 tahun dan bisa juga di atas 50 tahun. Colitis ulseratif terjadi pada 35-100 orang untuk setiap 100.000 di Amerika Serikat, atau kurang dari 0,1% dari populasi. Penyakit ini cenderung lebih umum di daerah utara. Meskipun kolitis ulserativa tidak diketahui penyebabnya, diduga adagenetik kerentanan komponen. Penyakit ini dapat dipicu pada orang yang rentan oleh faktor-faktor lingkungan. Meskipun modifikasi diet dapat mengurangi ketidaknyamanan seseorang dengan penyakit, kolitis ulserativa tidak diduga disebabkan oleh faktor-faktor diet. Meskipun kolitis ulserativa diperlakukan seolah-olah itu merupakan penyakit autoimun, tidak ada konsensus bahwa itu adalah seperti itu. Pengobatannya dengan obat anti-
peradangan, kekebalan, dan terapi biologis penargetan komponen spesifik dari respon kekebalan. Colectomy (parsial atau total pengangkatan melalui pembedahan usus besar) yang kadang-kadang diperlukan, dan dianggap sebagai obat untuk penyakit. G. TUJUAN
Agar mahasiswa mengetahui dan mengerti diit diit yang sesuai untuk penyakit Colitis BAB II TINJAUAN PUSTAKA
H. TINJAUAN PUSTAKA Colitis ulserativa merupakan suatu penyakit menahun di usus besar mengalani peradangan dan luka,yang menyebabkan diare berdarah,kram perut dan demam.kolitis ulserativa bisa dimulai pada umur berapapun,tapi biasanya dimulai antara umur 15-30 tahun. tidak seperti crohn,colitis ultrativa tidak selalu menoengaruhi seluruh ketebalan dari usus dan tidak pernah mengenai usus halus.penyakit ini biasanya di mulai di rectum atau kolon sigmoid dan akhirnya menyebar ke sebagian atau seluruh usus besar.Sekitar 10% penderita hanya mendapat satu kali serangan.. Proktitis ulserativa merupakan peradangan dan perlukaan di rectum.pada 10-30% penderita penyakit ini akhirnya menyebar ke usus besar.jarang diperlakukan pembedahan dan harapan hidupnya baik. Penyebab penyakit ini tidak diketahui,namun factor keturunan dan respon sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif di usus,diduga berperan dalam terjadinya jolitis ulserativa. Suatu serangan ini bisa mendadak dan berat,menyabebkan diare hebat,demam tinggi,sakit perut,dan peritonitis(radang selaput perut) selama serangan penderita tampak sangat sakit.Yang lebih sering terjadi adalah serangannya dimulai secara bertahap,dimana penderita memiliki keinginan untuk buang air besar,kram ringan pada perut bawah dan tinja yang berdarah dan berlendir. Jika penyakit ini tervatas pada rectum dan kolon sigmoid tinja mungkin normal,kering,dank eras.tetapi ketika buang air besar ,dari rectum keluar lender yang banyak mengandung sel darah merah dan sel darah putih.Gejala lain bisa demam. Jika menyebar ke usus besar ,tinja akan lunak dan penderita dapat buang air besar sebanyak 10-20 kali/hari.Tinja tampak mengandung nanah,darah dah lendir. Anonim. by: oktober 2011 2011. http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/colitis/. Posted
Kebanyakan gejala Colitis ulserativa pada awalnya adalah berupa buang air besar yang lebih sering. Gejala yang paling umum dari kolitis ulseratif adalah sakit perut dan diare berdarah. Pasien juga dapat mengalami: 1. Anemia 2. Fatigue/ Kelelahan 3. Berat badan menurun 4. Hilangnya nafsu makan 5. Hilangnya cairan tubuh dan nutrisi 6. Lesi kulit (eritoma nodosum) 7. Lesi mata (uveitis) 8. Nyeri sendi 9. Kegagalan pertumbuhan (khususnya pada anak-anak) 10. Buang air besar beberapa kali dalam sehari (10-20 kali sehari) 11. Terdapat darah dan nanah dalam kotoran. 12. Perdarahan rektum (anus). 13. Rasa tidak enak di bagian perut. 14. Mendadak perut terasa mulas. 15. Kram perut. 16. Sakit pada persendian. 17. Rasa sakit yang hilang timbul pada rectum 18. Anoreksia 19. Dorongan untuk defekasi Pengobatan ditujukan untuk mengendalikan peradangan mengurangi gejala dan mengganti cairan dan zat gizi yang hilang.penderita sebaij\knya mengurangi makanmakan sayur mentah untuk mengurangi cedera fisik pada lapisan usus besar yang meradang.Diet bebas susu,dan minum obat antikolinergik.Apabila sudah terjadi colitis toksis maka penderita harus diawasi,semua obat dihentikan dan pasien dipuasakan.Jika pasien masih lemah dapat dilakukan tindakan pembedahan. Moorhouse,Dongoes.2000.Rencana Asuhan Keperawatan.Edisi 3.Jakarta:EGC
BAB III HASIL, PERHITUNGAN, & PEMBAHASAN I. HASIL J. PERHITUNGAN Diketahui : Seorang Ibu H dengan U = 51 tahun, BB = 40 kg, TB = 140 cm, TL = 45 cm . Pada tanggal 1 juli 2013 px datang ke RS dengan mengeluh BAB sakit disertai darah, perut melilit 6 hari terakhir, BAB pagi lembek, BAB sekitar jam 10 berlendir, serta selalu merasa sakit sebelum dan sesudah BAB , Dokter mendiagnosa px menderita penyakit Colitis. 1 thn yang lalu , px pernah dirawat di rumah sakit selama 12 hari karena colitis, px merupakan seorang ibu rumah tangga. Pemeriksaan klinis : TD : 120/70 mmHg, RR : 20 x /mnt, adi : 0 / mnt, Suhu : 3 Pemeriksaan Biokimia : HB LEUKOSIT 12,2 7450
HEMATOKRIT 38 ERITROSIT TROMBOSIT MONOSIT SGOT SGPT ANTROPOMETRI : IMT = BB/TB = 40 /(1,4)2 = 40/1,96 = 20,40 -> NORMAL BBI = (TB-100) = 140-100 = 40 Kg 4,3 331.000 9,7 19 29
BEE = 655 + (9,6 X BB) + (1,7 X TB) (4,7 X U) = 655 + (9,6 X 40) + (1,7 X 140) (4,7 X 57) = 1037,3 kkal TEE = BEE x FA x FS = 1037,3 x 1,2 x 1,2 = 1493,712 kkal Protein = 15 % x 1493,712 kkal / 4 = 56,01 gr. Lemak = 20 % x 1493,712 / 9 = 33,19 gr Karbohidrat = 65 % x 1493,712 / 4 = 242,742 gr K. PEMBAHASAN Pada Praktikum ini kami membahas tentang berbagai penyakit seperti, IBD, kantung empedu, colitis, sirosisdan juga thypoid. Namun pada kelompok kami membahas tentang penyakit colitis . Colitis adalah peradangan akut ataupun kronik pada kolon yang mana dapat menyebabkan perut melilit dan diare berdarah . untuk itu pada penyakit colitis ini, memiliki beberapa diagnose gizi yang mana berpengaruh terhadap intervensi yang akan diberikan. Pada pasien colitis ini diagnose yang diberikan seperti NB1.4 yaitu kurangnya memonitor diri sendiri yang berkaita dengan kesulitan mengatur waktu yang ditandai dengan tidak memiliki waktu untuk berolahraga dan waktu tidur kurang dari 4 jam . Selain itu juga, diagnose yang diberikan berhubungan dengan penurunan kebutuhan serat disebabkan adanya peradangan usus ditandai oleh BAB berdarah. Oleh karena itu,maka diberikan intevensi diet rendah sisa dan rendah serat yang mana syarat diitnya porsi kecil tapi sering, cukup cairan dan elektrolit, makanan yang diberikan juga pada diet rendah sisa adalah makanan saring. Hal ini karena adanya peradangan di usus jadi diberikan bentuk makanan yang mudah dicerna. Adapun tujuan diberikan diit tersebut adalah untuk memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, mencegah iritasi, mengistirahatkan usus pada masa akutdan juga sebagai proses dari adaptasi terhadap bentuk makanan yang lebih padat dan untuk memonitoring dan evaluasi maka perlu diperhatikan apakah BAB nya masih berdarah dan berlendir atau tidak. BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN L. KESIMPULAN Pada praktikum ini membahas tentang IBD,Sirosis, Colitis, Kantung Empedu, dan Thypoid. Yang terpenting yang perlu di ingat adalah bagaimana dalam cara menganalisis diagnose gizi dan intervensi pasien dan juga perencanaan menu pasien. M. SARAN Perlu memperhatikan dalam penentuan diagnosis dan intervensi.
A. JUDUL PRAKTIKUM
B. HARI/TGL PRAKTIKUM : RABU, 20 MARET 2013 C. PRAKTIKUM KE D. KELOMPOK KE : I (SATU) : 3 (TIGA)
E. NAMA KELOMPOK : -Feriskayanti H -Fenny Kurniawaty -Natalis Kurnianda
BAB I PENDAHULUAN & TUJUAN F. PENDAHULUAN G. TUJUAN BAB II TINJAUAN PUSTAKA H. TINJAUAN PUSTAKA
BAB III HASIL, PERHITUNGAN, & PEMBAHASAN I. HASIL J. PERHITUNGAN K. PEMBAHASAN BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
L. KESIMPULAN M. SARAN
Anda mungkin juga menyukai
- Kerangka Acuan Kelas Ibu HamilDokumen3 halamanKerangka Acuan Kelas Ibu HamilFriska Hutahaean89% (9)
- Contoh SOP KebidananDokumen13 halamanContoh SOP KebidananFriska Hutahaean73% (11)
- Sap LansiaDokumen7 halamanSap LansiaFriska Hutahaean100% (1)
- Instrumen Penilaian Kantin SehatDokumen1 halamanInstrumen Penilaian Kantin SehatFriska Hutahaean100% (3)
- Sang GauDokumen13 halamanSang GauFriska HutahaeanBelum ada peringkat
- Kartu Stock Obat'12Dokumen2 halamanKartu Stock Obat'12Friska HutahaeanBelum ada peringkat
- Kuesioner RemajaDokumen2 halamanKuesioner RemajaFriska HutahaeanBelum ada peringkat
- Bahan Campuran MakananDokumen22 halamanBahan Campuran MakananFriska HutahaeanBelum ada peringkat
- Laporan Akhir Ipl 03Dokumen189 halamanLaporan Akhir Ipl 03Friska Hutahaean100% (1)
- Proposal SeminarDokumen15 halamanProposal SeminarFriska HutahaeanBelum ada peringkat
- Feris HaccpDokumen76 halamanFeris HaccpFriska HutahaeanBelum ada peringkat
- Laporan Pertanggung Jawaban Seminar Hari SelasaDokumen6 halamanLaporan Pertanggung Jawaban Seminar Hari SelasaFriska Hutahaean50% (2)
- Laporan Besar - Umbi-UmbianDokumen19 halamanLaporan Besar - Umbi-UmbianFriska HutahaeanBelum ada peringkat
- Pembuatan KerupukDokumen12 halamanPembuatan KerupukFriska Hutahaean100% (1)
- Perbedaan Uji Benedict Dan Uji FehlingDokumen1 halamanPerbedaan Uji Benedict Dan Uji FehlingFriska Hutahaean67% (6)
- Pembuatan KerupukDokumen12 halamanPembuatan KerupukFriska Hutahaean100% (1)
- Poa Asi EksklusifDokumen2 halamanPoa Asi EksklusifFriska Hutahaean100% (1)
- Laporan Pembuatan KopiDokumen2 halamanLaporan Pembuatan KopiFriska HutahaeanBelum ada peringkat
- Laporan Pembuatan KopiDokumen2 halamanLaporan Pembuatan KopiFriska HutahaeanBelum ada peringkat
- Serat Larut Dan Serat Tidak Larut Dalam Bahan MakananDokumen1 halamanSerat Larut Dan Serat Tidak Larut Dalam Bahan MakananFriska HutahaeanBelum ada peringkat