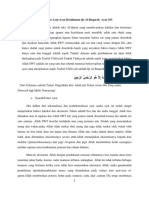Hakikat Bahasa Menurut Sokrates Plato Da
Hakikat Bahasa Menurut Sokrates Plato Da
Diunggah oleh
Devi Yulianti Wafiah0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
9 tayangan2 halamanJudul Asli
Hakikat_Bahasa_menurut_Sokrates_Plato_da (1).docx
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
9 tayangan2 halamanHakikat Bahasa Menurut Sokrates Plato Da
Hakikat Bahasa Menurut Sokrates Plato Da
Diunggah oleh
Devi Yulianti WafiahHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 2
Bangsa Yunani pada masa Pra Sokrates menyebut bahwa bahasa
merupakan media pengungkapan daya magis dalam komunikasinya
dengan para Dewa dengan kekuatan supernatural lainnya (Kaelan,
2009:22). Pendapat tersebut tergoyahkan karena masyarakat yang hidup
pada zamannya mulai mencium keganjilan. Adakah kekuatan magis yang
timbul melalui bahasa dapat memengaruhi alam dan benda-benda yang
meskipun demikian bahasa bukanlah tanpa potensi dan tanpa arti.
Kemudian Sokrates mencoba meluruskannya dengan menggunakan
metode dialektis-kritis, yaitu dialog antara dua pendirian yang
bertentangan atau merupakan perkembangan pemikiran dengan memakai
pertemuan antaride. Sokrates tidak mentah-mentah menelan beberapa
pemikiran yang ada, khususnya untuk mengetahui apa sebenarnya
hakikat bahasa itu. Ia menyarikan beberapa pemikiran yang ada sehingga
muncullah sarian baru miliknya yakni menjelaskan konsep-konsep filosofis
melalui bahasa. Konsep-konsep filosofis melalui bahasa tentunya untuk
mengetahui apa sebenarnya hakikat bahasa itu sendiri.
Perkembangan bahasa tak berhenti pada saat itu saja, juga pada
zaman Plato. Sebenarnya Plato tak serta merta membuat pemikiran baru
tentang bahasa, ia meneruskan pemikiran filsuf sebelumnya, yakni
Sokrates. Plato merumuskan bahwa semua bahasa berasal dari peniruan
bunyi-bunyi (Kaelan, 2009:28). Hanya saja nampak tak ada
kesinambungan antara keduanya, namun memerjelas apa sebenarnya
hakikat bahasa itu sendiri.
Agak berbeda dengan pemikiran Plato, Aristoteles (muridnya)
kemudian mengembangkan lagi menuju keterbenderangan mengenai
haikat bahasa. Aristoteles menyebutkan bahwa hakikat bahasa mendasar
pada prinsip metafisisnya (Kaelan, 2009:30). Aristoteles tidak sependapat
dengan pendapat gurunya yang mengemukakan bahwa semua bahasa
berasal dari peniruan bunyi-bunyi saja, melainkan ada hal lain yang
melatarbelakanginya. Hal tersebut yakni hakikat dan bentuk yang tentu
saja memiliki makna di dalamnya. Selain itu, Aristoteles juga
mengembangkan prinsip keteraturan dalam bahasa sehingga bahasa
memiliki paradigma yang disebut dengan analogi (Kaelan, 2009:31).
Simpulan mengenai kesejarahan antara ketiga filsuf tersebut
bahwa munculnya definisi tidak berawal dari kekosongan belaka. Ada
bekal sebelumnya. Entah itu dari kebudayaan masyarakat atau definisi
filsuf sebelumnya. Tentunya mengalami proses penyarian secara
mendalam untuk memunculkan suatu definisi baru mengenai hakikat
bahasa.
Sederhananya, perbedaan hakikat bahasa menurut para filsuf
tersebut terletak pada dasar yang mereka gunakan. Seperti Sokrates,
dasarnya adalah kebudayaan dari masyarakat yang hidup disekitarnya.
Lain lagi dengan Plato dan Aristoteles yang mengaji lebih rinci dan
mendalam dari filsuf yang ada sebelum mereka. Plato pada Sokrates dan
Aristoteles pada Plato.
Anda mungkin juga menyukai
- 4.Rpp Bunyi 1dan 2Dokumen19 halaman4.Rpp Bunyi 1dan 2Devi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- Lembar Pengesahan ADM GURU 2019Dokumen2 halamanLembar Pengesahan ADM GURU 2019Devi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- SMK Dharma AgungDokumen15 halamanSMK Dharma AgungDevi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- Undangan Pemateri Ibu NazmiDokumen2 halamanUndangan Pemateri Ibu NazmiDevi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- Uas KimiaDokumen4 halamanUas KimiaDevi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- Optimal SolutionDokumen9 halamanOptimal SolutionDevi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- Fungsi Dan Peningkatan UtilitasDokumen16 halamanFungsi Dan Peningkatan UtilitasDevi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- CONTOHDokumen1 halamanCONTOHDevi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- Analisis Kandungan Ayat Tafsir Abyu GGDokumen3 halamanAnalisis Kandungan Ayat Tafsir Abyu GGDevi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- Aliran MaturidiyyahDokumen18 halamanAliran MaturidiyyahDevi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- Abiyyu GGDokumen4 halamanAbiyyu GGDevi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- Problematika Peserta DidikDokumen9 halamanProblematika Peserta DidikDevi Yulianti WafiahBelum ada peringkat
- Menafsirkan Kehendak TuhanDokumen15 halamanMenafsirkan Kehendak TuhanDevi Yulianti WafiahBelum ada peringkat