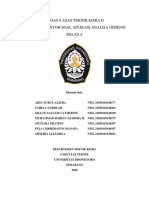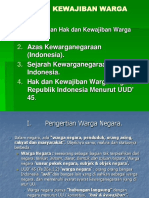Pancasila Fils NKRI
Pancasila Fils NKRI
Diunggah oleh
Julia Gabriel0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
15 tayangan26 halamanJudul Asli
Pancasila Fils NKRI.pptx
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
15 tayangan26 halamanPancasila Fils NKRI
Pancasila Fils NKRI
Diunggah oleh
Julia GabrielHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 26
PANCASILA: FILSAFAT
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
a. Pengertian Filsafat & Pemikiran Filsafat.
b. Pancasila:Hasil Pemikiran Filsafat.
c. Karakteristik Filsafat Pancasila.
d. Hakekat Sila-sila Pancasila.
I. PENGERTIAN FILSAFAT & PEMIKIRAN FILSAFAT.
a. Pengertian Filsafat.
Philien: Cinta, Senang, Suka;
Shopia: Kebijaksanaan.
Philoshopia: “Cinta, suka, senang terhadap kebijaksanaan”.
Kebijaksanaan: keputusan berdasar “kebenaran” (logika) dan
“kebaikan” (moral) atas pertimbangan “kemanusiaan”.
Menurut Louis Katshof;
Filsafata: aktivitas berfikir dilakukan secara “Cermat dan Serius”.
Cermat: pemikiran dengan mempertimbangkan segala aspek
yang ‘berkaitan langsung’ dan ‘tidak langsung’, yang ‘tampak’
maupun yang ‘tidak tampak’ dengan segala kemungkinanya.
Serius: memperoleh jawaban ‘esensial‘ (tak terbantahkan).
Jawaban yang tidak sekedar ‘fungsional’ atau ‘kegunaanya’.
b. Pemikiran Filsafat.
Filsafat: Ilmu, pemikiran filsafat harus menemukan
“kebenaran” keilmuan.
Ciri-ciri pemikiran filsafat:
a. Logis: berdasar pada ‘logika’, pemikiran harus dapat
difahami dengan ‘akal sehat’.
b. Komprehensif: pemikiran bersifat ‘menyeluruh’,
memperhatikan seluruh aspek yang berhubungan,
langsung, tidak langsung, fisis dan non fisis. Hasil pemikiran
bersifat ‘mendasar’ atau ‘substansi’ dan ‘esensi’.
c. Sistematis: pemikiran bersifat ‘urut’ dan ‘runtut’.
Urut: menunjukkan pemikiran yang teratur secara
‘induktif-deduktif’ atau ‘deduktif-induktif’.
Runtut: pemikiran tidak ‘loncat-loncat’, ‘dikotomi’ dan
tidak ‘paradog’.
d. Kritis: motifasi untuk ‘selalu ingin tahu’ (mengetahui) segala
sesuatu, dan ‘tidak mudah percaya’ (berhenti) sebelum
membuktikan.
e. Objektif: pemikiran yang sesuai dengan ‘fakta’ dan ‘data
empiris’.
Fakta: gambaran tentang objek yang terdapat pada
‘pikiran’.
Data: ‘kenyataan di lapangan’ tentang objek tersebut.
Empiri: objeh yang dapat diamati dengan ‘inderawi’
manusia.
f. Universal: hasil pemikiran menunjukkan “kebenaran” yang
tidak terikat “ruang, waktu, dan tempat”.
II. PANCASILA: HASIL PEMIKIRAN FILSAFAT.
Pancasila: sengaja di buat oleh “Faunding Father” (BPUPKI &
PPKI). Prosesnya melalu ‘perdebatan, adu argumen, dan
diskusi’ dalam forum ‘formil’ (BPUPKI & PPKI) dan ‘non formil’ (di luar
sidang Panitia IX).
Perdebatan (diskusi) resmi: untuk menyusun “Rancangan Dasar
Negara” – “PANCASILA”, (BPUPKI, Panitia IX, PPKI).
SIDANG BPUPKI (30 Mei – 1 Juni 1945)
Dalam sidang terdapat “3 (tiga) tokoh” yang menyampaikan
“pemikiran” tentang Rancangan (calon) Dasar Negara.
1. Prof. dr. Soepomo.
Sebelum berfikir ‘Dasar Negara’, tentukan dulu “Azas Negara”
atau ‘teori negara’ yang di anut.
a. Teori Individualistik (liberalisme) - Tms Hobbes.
Negara: ‘persekutuan individu-individu’ yang bersatu, dan
persekutuan berdasarkan “aturan atau ketentuan” yang menjamin
“kebebasan” masing-masing individu. Jika peraturan negara tidak
menjamin kemerdekaan setiap individu, tidak mungkin bersatu.
Teori Individualistik: ‘tdk cocok bagi bangsa Indonesia’; sebab
mengutamakan ‘kebebasan mutlak’ kepada setiap individu.
b. Teori Kelas (Teori Sosial, Claas Teoiry) Karl Marx &
Leinin (15-16).
Negara: kekuasaan yang diraih melalui “persekutuan
masyarakat kelas” tertentu (kelompok sosial masyarakat)
tertentu untuk menindas kelas (kelompok) yang lain.
‘Negara: simbol kekuasaan’, dipergunakan oleh
penguasa (kelompok) untuk ‘menindas kelompok lain’.
Teori kelas tidak cocok bagi bangsa Indonesia, setiap
kelompok masayarakat selalu berhadapan, berebut
kekuasaan, dan saling menindas.
c. Teori Integralistik (Spinoza & Hegel 16-17).
Negara: “hasil perjuangan seluruh masyarakat tanpa
kecuali”. Bukan hasil dari sekelompok masyarakat
tertentu, golongan tertentu, atau individu tertentu.
Negara harus menjamin kepentingan masyarakat
seluruhnya tanpa kecuali, dan melindungi seluruh rakyat
sebagai “satu persatuan”. Negara tidak boleh memihak
kepada sekelompok masyarakat tertentu, golongan, apalagi
perseorang. Negara “harus melindungi seluruh warga
masyarakat sebagi satu kesatuan integral”. Negara: harus
mengusahakan terwujudnya masyarakat “Bhinneka
Tunggal Ika”, jauh dari “dominasi dan diskriminasi”. Teori
Integralistik: Azas disepakati forum.
Diusulkan pembentukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dan majelis perwakilan rakyat (DPR).
2. Mr. Moh. Yamin.
Mengusulkan 5 (lima) azas Dasar Negara:
1. Peri Ketuhanan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Kesatuan.
4. Peri Kerakyatan (demokrasi).
5. Peri Keadilan Sosial.
3. Ir. Soekarno.
Mengemukakan 5 (lima) azas Dasar Negara:
1. Internasionalisme (kemanusiaan).
2. Nasionalisme (persatuan)
3. Gotong royong (demokrasi)
4. Keadilan Sosial.
5. Ketuhanan Yang berkebudayaan.
Kelima azas (usul kawan ahli bahasa) diberi nama
“Pancasila”.
PANITIA IX (17-22 Juli 1945).
Diskusi & adu argumentasi menentukan ‘Rancangan Dasar
Negara’ dilakukan Panitia IX (22 Juli 1945) hasilkan “Piagam
Jakarta” atau ‘Jakarta Carter’:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan menjalankan syariat
Islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
SIDANG PPKI (18-8-1945).
Sebelum sidang telah disepakati “perubahan” pada rumusan
Dasar Negara; seperti tertulis dalam Pembukaan UUD’45:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berdasar proses histori, Pancasila sengaja dibuat sebagai “Dasar
Negara”. Artinya: sebagai “landasan untuk menyelenggarakan
pemerintahan negara di pusat dan daerah”, dan sebagai
“landasan kegiatan bagi para penyelenggara negara dan warga
negara seluruhnya”.
Pancasila Dasar Negara: hasil pemikiran para “faunding fathers”;
hakekatnya merupakan “Filsafat Negara Republik Indonesia”.
Hasil pemikiran para pendiri negara Indonesia; berarti Pancasila
Dasar Negara: “Karya besar bangsa Indonesia” atau ‘hasil kreasi
bangsa Indonesia’ yang layak dihargai dan dibanggakan.
Kedudukannya “sama” dengan ‘Filsafat Liberalisme’ dan ‘Filsafat
Sosialisme’: sebagai ‘Dasar Negara’ atau ‘Filsafat Negara’.
Bangsa Indonesia layak bangga; filsafat negara yang dipilih:
“buah pikiran (filsafat) bangsa sendiri”, di beri nama “Pancasila”.
Filsafat Pancasila: diangkat dari “budaya original bangsa
Indonesia”, yang menjadi simbol ‘Budaya Nasional Indonesia’.
III.KARAKTERISTIK FILSAFAT PANCASILA.
Pancasila Filsafat Negara: “sistem nilai” yang terdiri 5 (lima)
sila, sebagai ‘satu kesatuan mutlak’. Artinya tidak boleh dan
tidak bisa di tiadakan 1 (satu) sila sekalipun. Sebagai “sistem
nilai”, filsafat Pancasila memiliki ciri-ciri:
1. Bersifat Organis.
Kelima sila pancasila: satu kesatuan sistem nilai bersifat “mutlak”
dan “saling berhubungan secara organis”. Mutlak: setiap sila harus
ada. Berhubungan organis: setiap sila saling berkaitan satu sama
lain dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri meski dalam posisi dan
fungsi berbeda.
2. Bersifat HierarKhis Berbentuk Piramid.
Kelima sika pancasila: satu kesatuan sistem nilai yang
menggambarkan susunan (tingkatan) kualitas dan kuantitas, luasan
ruang lingkup, yang saling berkorelasi dalam bentuk segitiga.
3. Bersifat Saling Menjiwai dan merefleksi.
Kelima sila pancasila: satu kesatuan sistem nilai yang
mempunyai korelasi “saling menjiwai dan merefleksikan makna”
di antara sila satu dengan sila-sila yang lain.
4. Fundamental Norm.
Pancasila Dasar Negara: “norma fundamental bagi NKRI”,
bersifat ‘mutlak’. 5 (lima) sistem nilai dalam Pancasila harus
menjadi “landasan dasar” bagi penyelenggaraan NKRI, dan
harus dikonkritkan dalam “Hukum Dasar Negara” yang tertulis.
Kelima sistem nilai Dasar Negara: “mengikat dan memaksa”
segenap penyelenggara negara, dan warga negara seluruhnya
tanpa kecuali. Sebab kelima sistem nilai sudah menjilma menjadi
“hukum dasar tertulis” alias “konstitusi NKRI”: UUD’45.
5. Sesuai 4 (empat) Syarat Filsafat.
a. Causa Material: Asal mula bahan dari budaya bangsa.
b. Causa Efisien: asal mula tujuan, sebagai dasar negara.
c. Causa Formalis: asal mula bentuk, sengaja di buat melalui
perdebatan dan diskusi pada forum sidang BPUPKI, Panitia IX,
dan sidang PPKI.
d. Causa Finalis: asal mula karya, sesudah selesai di bentuk dan
ditetapkan menjadi Dasar negara pada tanggal 18-8-1945;
merupakan hasil karya bangsa Indonesia.
IV. HAKEKAT SILA-SILA PANCASILA.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Subjek pokok: “Tuhan”. Diberi awalan ‘ke’ akhiran ‘an’:
“sifat-sifat Tuhan”.
Maha: ‘besar’ atau ‘lebih’. Esa: “abadi” atau “kekal”.
Bangsa Indonesia harus percaya dan yakin terhadap sifat
“Tuhan Yang Besar, Kekal, dan Abadi”; sebagai “kausa
prima”: sebab segala makhluk yang ada di alam semesta.
Tuhan sebagai “kausa Prima” bermakna: setiap manusia
Indonesia, bangsa Indonesia, dan Negara Indonesia ‘asal
mulanya’ adalah dari ‘Tuhan’. Kepercayaan dan keyakinan ini:
“Ciri Karakteristik” bangsa Indonesia; sebagai “bangsa
religius”. (Pemb. UUD’45, al. 3)
Tuhan menciptakan manusia Indonesia (bangsa Indonesia):
bersifat “Jamak, Plural, Majemuk”, dan tidak Tunggal. Kodrat
atau fitrah bangsa Indonesia: berbeda jenis, suku bangsa, lokal
(wilayah daerah), keyakinan dan kepercayaan, kebudayaan
(adat-istiadat, bahasa, kesenian dll). Perbedaan kodrati: “tidak
elok” dipertentangkan, justru dipahami alasanya agar ‘positif’.
Berdasar Ketuhan Yang Maha Esa: “kausa prima”, bangsa
Indonesia dapat ‘hidup bersama dan berdaulat’ dalam
“Bhinneka Tunggal Ika”. Atas dasar Ketuhan Yang Maha Esa:
perbedaan kepercayaan dan keyakinan kepada “Tuhan” yang
“Besar, Kekal, Abadi” di jamin “kemerdekaanya” oleh bangsa
dan negara Indonesia.
Berdasarkan makna sila Ketuhanan Yang Maha
Esa, Indonesia:
1. Negara “Monotheis”.
Negara mengakui, yakin, dan percaya kepada “Tuhan
Yang Besar, Kekal, dan Yang Abadi”. Indonesia: bukan
negara “Agama”, bukan negara “Atheis”, atau “Sekuler”.
2. Negara memandang keyakinan dan kepercayaan
kepada Tuhan Yang Kekal dan Abadi: “hak azasi
manusia yang hakiki”. Keyakinan dan kepercayaan
kepada Tuhan dan agama: “Fitrah Tuhan kepada
manusia”, maka tidak bisa di tekan, di paksa, dan
dirampas oleh siapapun juga termasuk negara.
Keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan dan agama:
bukan pemberian negara, bangsa, masyarakat,
keluarga, dan orang tua; tetapi “anugrah Tuhan”.
3. Negara “menjamin kemerdekaan” setiap warga negara
dan penduduk, dalam menjalankan keyakinan dan
kepercayaannya kepada Tuhan dan agama,
melaksanakan ibadah menurut keyakinan dan
kepercayaan masing-masing.
4. Negara “berhak dan wajib melindungi, memelihara,
dan membina kerukuan antar umat beragama” dalam
menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka
terhadap Tuhan Yang Besar, Kekal, dan Abadi.
5. Negara menganut “nilai mutlak”.
Keyakinan kepada Tuhan sebagai “kausa prima”:
manusia, bangsa, dan negara Indonesia “asal mulanya
dari Tuhan”. Segala tindakan, perbuatan, dan
keputusan manusia Indonesia, warga negara, dan para
penyelenggara negara: harus dipertanggungjawabkan
secara “hukum negara” dan “hukum Tuhan”.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Subjek pokok: “manusia” harus sesuai sifat-sifatnya: ‘adil’
dan ‘beradab’ (bukan biadab). Adil: tidak memihak, atau
seimbang. Beradab: “berbudipekerti luhur”, menghargai
“harkat martabat” manusia sebagai “makhluk Tuhan”.
Menurut bangsa Indonesia, manusia: bukan makhluk
“individu” (Thomas hobes dalam Liberalisme) atau
makhluk “sosial” (Karl Maxs dalam Sosialisme). Manusia:
makhluk “monoplural” (majemuk tunggal) sekaligus
“monodualis” (dwi tunggal). Monoplural: terdiri “struktur
kodrat, sifat kodrat, kedudukan kodrat”; monodualis:
“jasmani-rokhani, individu-sosial, pribadi mandiri-makhluk
Tuhan”. (Noto Nagoro, dan Driyarkara).
Dalam perspektif bangsa Indonesia, manusia: “sama
kedudukan”-nya dihadapan Tuhan , sebagai ‘makhluk’.
Artinya ‘Ciptaan’ harus tunduk, patuh pada ‘Pencipta’.
Menurut hukum Tuhan, sesama makhluk: ‘wajib dan harus’
saling menghormati, menghargai harkat dan martabat
kemanusiaan, tolong-menolong. Bukan menindas, menjajah,
menakhlukkan, mendominasi, mendiskriditkan,
menghancurkan dan memusnahkan.
Berdasarkan makna sila ke 2, bangsa dan negara Indonesia
menempatkan manusia di dunia: “sederajad”, tidak terbatas
‘ruang, waktu, tempat maupun status sosial’. Disebut:
“Internasionalisme manusia”.
Atas dasar penjelasan tsb, makna Kemanusiaan Yang Adil
dan Beradap:
1. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi “budipekerti luhur”:
menghormati “harkat martabat” manusia.
2. Manusia (Indonesia): Makhluk “Majemuk Tunggal” dan
“Dwi Tunggal”.
3. Kedudukan manusia: ‘sama’, sebagai “Makhluk” atau
‘Ciptaan’ harus patuh, tunduk kepada ‘Pencipta’.
4. Sesama manusia (makhluk): “wajib saling menghargai,
menghormati, dan tolong-menolong”. Bukan menindas,
menjajah, menakhlukkan, menghancurkan, dan
memusnahkan.
5. Manusia di muka bumi: “sederajad”, tanpa batas “ruang,
waktu, tempat, dan status sosial”. Manusia yang adil dan
beradab: rasa kemanusiaan bersifat “Internasionalisme”.
(Soekarno).
3. Persatuan Indonesia.
Subjek pokok: “satu”, awalan ‘per’ akhiran ‘an’: sifatnya
“tunggal” atau seperti “satu”.
Indonesia (James Richardson Logan): masyarakat yang
berdomisili di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samodra,
terdiri dari berbagai suku bangsa, memiliki kebudayaan “unik”,
dan hidup berdampingan secara harmonis.
Bangsa Indonesia: “bhinneka” (Sabang – Meraoke) telah
mengikrarkan diri sebagai bangsa “Tunggal Ika” yaitu:
sebagai bangsa yang satu, “bangsa Indonesia”. Realita ini:
bukti nyata berkembangnya rasa “cinta tanah air”, semangat
“Nasionalisme Indonesia”, serta “bangga menjadi bangsa
Indonesia”.
Rasa cinta tanah air Indonesia dan bangga menjadi bangsa
Indonesia: semangat “nasionalisme Indonesia” yang harus
ditumbuh-kembangkan kepada segenap warga dari berbagai
suku bangsa, budaya, agama, dan kepercayaan. Tujuannya
agar semangat “nasionalisme Indonesia” dapat berkembang
luas hingga menumbuhkan rasa “cinta dan bangga” pada
“Dasar Negara, Bentuk Negara, Sistem Tatanegara, dan
Tujuan Negara”.
Nasionalisme Indonesia, cinta tanah air dan rasa bangga
menjadi bangsa Indonesia harus terus dipelihara, jangan
sampai tersesat pada sifat “Chaufinisme”. Semangat
nasionalisme “sempit” menjadi “congkak & sombong”.
Berdasarkan sila ketiga, mengandung makna:
a. Bangsa Indonesia: bangsa bhinneka, yang
mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang “satu”
atau “tunggal”.
b. Bangsa yang “harmonis dan rukun” dalam hidup
berdapingan dengan suku bangsa berbeda, agama
dan kepercayaan berbeda, serta kebudayaan
berbeda (adat istiadat, bahasa, kesenian).
c. Nasionalisme Indonesia: “kesadaran segenap warga”
bahwa “dirinya”: sebagai bangsa Indonesia. Memiliki
rasa “cinta Tanah Air, bangga menjadi bangsa
Indonesia”, bangga kepada “Dasar negara”, cinta
kepada “Bentuk Negara”, “Sistem Tatanegara
Indonesia”, dan berusaha mewujudkan “Tujuan
Negara”.
d. Nasionalisme Indonesia tidak boleh bersifat
“Chaufinisme”.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan / Perwakilan.
Subjek pokok: “rakyat”, - ‘ke’ dan ‘an’: sifat sesuai kehendak
rakyat. “Kedaulatan Negara”: di tangan Rakyat.
Rakyat: ‘jamak’. Relita yakyat Indonesia: dari berbagai suku
bangsa, daerah, budaya, agama, pendidikan, dan
kepentingan atau keinginan yang berbeda. Guna
merealisasikan keinginan bersama yang berbeda-beda: perlu
“perencanaan, pemetaan, penataan (skala prioritas) dan
kesadaran” seluruh yakyat. Harus ada “sistem demokrasi”.
Sistem demokrasi: “Konstirusional” dan “Mutlak”. Dari dua
macam terdapat tiga jenis sistem demokrasi: “Demokrasi
Langsung, Demokrasi Perwakilan, dan Demokrasi campuran”.
Menurut sila ke 4: Indonesia menganut sistem demokrasi
“konstitusional”, dalam bentuk “Perwakilan”. (UUD’45, Bab
I, Ps. 1, a. 1 dan 2). Disebut : “Demokrasi Pancasila”.
Kehendak rakyat: prakteknya harus ‘dipimpin’, (dipandu,
diarahkan) oleh ‘hikmat’ agar mencapai ‘kebijaksanaan’;
melalui “musyawarah” dan atau “perwakilan”.
Musyawarah: dilakukan atas kesadaran (semangat)
“kekeluargaan, persaudaraan, dan gotong-royong”. Atas
dasar ‘kerelaan dan keiklasan’ dari semua anggota keluarga
dan saudara. Tujuannya: meraih yang berguna/ bermanfaat
bagi seluruhnya.
Seluruh rakyat dari berbagai suku bangsa, daerah, golongan
(budaya, agama, profesi, dsb); harus meiliki “wakil
representatif dan kompeten” pada sistem demokrasi.
Peran dan kedudukan “Wakil Rakyat”: sangat ‘vital’ bagi
terwujudnya “kehendak rakyat”; pengemban amanat
“kedaulatan Rakyat” melalui ‘kontrak politik: “Pemilu”.
Makna sila ke 4:
1. Kedaulata Negara:ada “di tangan rakyat” (Republik).
2. Rakyat: “jamak”, perlu sistem untuk menjalankan
kedaulatan rakyat, - “sistem demokrasi”.
3. Sistem demokrasi Indonesia: “Konstitusional”, berbentuk
“Perwakilan”. Sering disebut : “Demokrasi Pancasila”.
4. Wakil-wakil rakyat: di pimpin, di pandu atau di arahkan
untuk “musyawarah” secara “hikmat” guna mencapai
“kebijaksanaan”.
5. Dalam musyawarah dilandasi semangat “kekeluargaan,
persaudaraan, dan gotong-royong”; atas dasar “keiklasan
dan kerelaan” layaknya dalam keluarga dan saudara.
6. Wakil-wakil rakyat: harus memiliki “kompetensi” dan
‘merepresentasikan’ kondisi riil rakyat dan kehendaknya.
7. Peran dan kedudukan wakil rakyat: ‘vital’, pengemban
kedaulatan rakyat berdasarkan kontrak politik – ‘Pemilu’.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Subjek pokok: “adil”, sifat adil dari “negara” (organisasi
atau persekutuan hidup bersama: penyelenggara) yang
dapat dirasakan oleh “anggota atau rakyat Indonesia”
seluruhnya.
Sifat adil (keadilan): “Tujuan dibuatnya negara”, harus
diwujudkan secara nyata “dapat dirasakan” seluruh
rakyat Indonesia.
Keadilan sosial adalah prinsip keadilan bersifat:
a. Legal: adil secara “hukum, hak dan kewajibannya”.
b. Distributif: adil ‘pembegian danpenyaluran’, ‘tugas,
wewenang’ terhadap ‘hasilpembangunan’.
c. Komulatif: adil dalam “jumlah” (kuantitas) berdasar
“proporsi” dan “urgensi”-nya.
Makna sila ke 5:
1. Sifat adil dari “negara” (penyelenggara negara) kepada
“setiap anggota negara” (rakyat atau warga negara)
seluruhnya.
2. Sifat adil (keadilan): “Tujuan negara” yang harus
“direalisasikan”.
3. Sifat adil yang diwujud dalam bentuk:
Legal: resmi secara hukum.
Distributif: pembagian dan penyaluran tugas,
wewenang, dan hasil pembangunan.
Komulatif: proporsi dan urgensi.
= Jo Wo =
Anda mungkin juga menyukai
- Kelompok 5 PDFDokumen16 halamanKelompok 5 PDFAida AzjubaBelum ada peringkat
- TUGAS 6 - ATK 2 Kelas A - Kelompok 7 PDFDokumen13 halamanTUGAS 6 - ATK 2 Kelas A - Kelompok 7 PDFAida AzjubaBelum ada peringkat
- Tugas 5 Atk Rejim Termal NaturalDokumen3 halamanTugas 5 Atk Rejim Termal NaturalAida AzjubaBelum ada peringkat
- Hak Dan Kewajiban Warga NegaraDokumen11 halamanHak Dan Kewajiban Warga NegaraAida AzjubaBelum ada peringkat