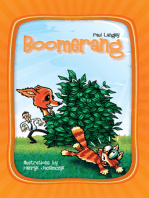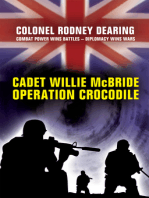Caping+cari Angin+kolom Tempo 22.06.2014-28.06.2014
Diunggah oleh
ekho1090 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
36 tayangan40 halamandiambil dari situs tempo.co
Judul Asli
Caping+cari angin+kolom tempo 22.06.2014-28.06.2014
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen Inidiambil dari situs tempo.co
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
36 tayangan40 halamanCaping+cari Angin+kolom Tempo 22.06.2014-28.06.2014
Diunggah oleh
ekho109diambil dari situs tempo.co
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 40
Kotor
Senin, 23 Juni 2014
Bagaimana menghakimi, ketika tak ada lagi yang tak berdosa? Ketika ukuran dosa dan bukan
dosa berganti? Ketika yang kotor dan suci jadi serba mungkin dan manusia makin tak
mengerti apa yang akan terjadi dengan sejarah?
Kita telah menyaksikanya, kita telah menempuh pembunuhan besar dan kecil. Kita bergulat
terus-menerus bagaimana seharusnya bersikap. Diam-diam kita berharap pada akhirnya
sejarah akan membawa kita ke sebuah keputusan yang diterima kapan saja oleh siapa saja.
Tapi tidakkah kita terlalu percaya kepada sejarah? "Bukankah sejarah selamanya tak
manusiawi, pembangun yang tak punya hati, yang mengaduk semennya dengan dusta, darah,
dan lumpur?"
Itu pertanyaan yang suram dalam novel Arthur Koestler, Darkness at Noon. Novel itu datang
dari pengalaman yang berbeda dengan pengalaman kita, tapi mungkin tak sepenuhnya
berbeda. Koestler menulisnya di akhir 1939 di Eropa ketika sejarah adalah pergolakan politik
yang gemuruh, bergairah, dan brutal. Baik gerakan Nazi (yang mau membangun Neue
Ordnung, "Orde Baru") maupun Komunisme (yang hendak membangun "Kehidupan Baru")
yakin bahwa sejarah akan bergerak dengan langkah pasti dan tak peduli ke arah yang
ditunjukkan cita-cita mereka, meskipun selalu "meninggalkan lumpur yang dibawanya
beserta mayat mereka yang tenggelam". Sejarah, dengan kata lain, tak pernah salah.
Dengan keyakinan itu, kekerasan dan pembunuhan tak bisa dikutuk.
Darkness at Noon tak menyebut di mana ceritanya berlangsung. Tapi pembaca akan tahu
bahwa peran utamanya, Nicholas Salmanovitch Rubashov, adalah seorang aktivis Partai
Komunis Rusia, tokoh fiktif yang dibentuk dari pengalaman sejati para pejuang Revolusi
Oktober yang ditembak mati kawan seperjuangan mereka sendiri, Stalin, ketika orang ini
memegang tampuk pimpinan. Rubashov adalah orang yang berjasa kepada Partai dalam
mengukuhkan kekuasaan, tapi kemudian dianggap berkhianat oleh Sang Ketua (disebut
sebagai "No. 1"). Ia disekap, disiksa, disuruh mengakui perbuatan yang tak pernah
dilakukannya, dan ditembak mati.
Tapi jangan-jangan Sang "No. 1" benar. Rubashov sendiri jadi ragu. Dengan keyakinannya
tentang sejarah, ia tak serta-merta sanggup mengatakan bahwa sang "No. 1" sewenang-
wenang. Orang-orang yang dibunuhnya mungkin akhirnya harus mengakui, meskipun dengan
peluru di tengkuk, bahwa penguasa tertinggi itu tak berdosa. Ia telah bertindak sebagai alat
sejarah untuk membangun dunia yang lebih baik. Ia ganas, tapi tak bisa dihakimi dengan
vonis yang meyakinkan.
"Tak ada kepastian," gumam Rubashov dalam selnya, tak berdaya. Kita hanya bisa naik
banding ke hadapan Sejarah (ditulis dengan huruf kapital "S"). Tapi yang tragis dalam hidup
manusia ialah bahwa keputusan Sejarah diberikan "hanya setelah rahang orang yang naik
banding itu sudah jadi debu bertahun-tahun yang lalu".
Sang hakim datang terlambat, selalu terlambat.
Tapi saya kira tidak. Saya kira ada yang salah dalam pandangan ini. Sejarah bukanlah hakim.
Ia bukan orakel sakti yang menebak. Sejarah tak berada di luar diri kita, dan kita tak berada
di luarnya, dan manusia bukan cuma sarananya. Kita tak perlu menuliskannya dengan huruf
kapital "S". Marx benar ketika ia mengatakan bahwa bukan sejarah yang menggunakan
manusia sebagai cara untuk mencapai tujuannya. "Sejarah hanyalah kegiatan manusia dalam
mengejar tujuan."
Artinya, manusia itulah yang hakim.
Tapi di sini juga persoalan tak mudah diselesaikan, ketika orang mulai mengatakan bahwa,
seperti konon kata Napoleon, bahkan "nasib adalah politik". Nasib, yang dianggap tak
terelakkan datang dalam hidup manusia, semakin dibaca sebagai hasil interaksi manusia,
zoon politikon. Tak ada ketentuan yang datang dari langit. Tak ada nilai yang tak tersentuh
pergulatan di bumi. Tak ada nilai yang universal yang ditentukan begitu saja.
Tapi jika demikian halnya, menghakimi akan mustahil. Ketika yang universal diasumsikan
tak pernah terjadi, ukuran guyah. Apa yang pada suatu keadaan dianggap "baik" pada
keadaan lain dianggap "jahat". Tak ada yang tak berdosa, ketika ukuran dosa dan tak berdosa
tiap kali bisa berganti.
Namun bisakah kita hidup tanpa menghakimi? "Aku harus mendapatkan keadilan, atau aku
akan menghancurkan diriku sendiri," kata Ivan Karamazov dalam novel Dostoyevsky yang
termasyhur itu. Dan bagi orang ini keadilan yang dikehendakinya bukan yang berada di
"ruang dan waktu yang tak terhingga". Ia menghendaki keadilan yang ada di bumi.
Yang diingatkan Ivan Karamazov ialah bahwa keadilan salah satu nilai yang universal
meskipun tak pernah penuh dan kekal di dalam hidup yang terbatas, sepenuhnya berharga.
"Atau aku akan menghancurkan diriku sendiri."
Goenawan Mohamad
KTP
Sabtu, 21 Juni 2014
Putu Setia
Nyonya Murtina mendadak pingsan di sebuah halte Trans Jakarta. Orang-orang panik karena
wanita ini datang sendirian. Petugas lantas membawanya ke rumah sakit terdekat untuk
mendapatkan perawatan. Syukur, kartu tanda penduduk (KTP) Murtina diketemukan. Segera
KTP itu dibawa ke bagian pendaftaran. Dengan memasukkan ke card reader, semua catatan
pribadi Murtina terungkap, termasuk riwayat kesehatannya. Setelah diberikan pertolongan,
pihak rumah sakit memasukkan riwayat kesehatan yang baru di KTP Murtina, tentang jenis
penanganan dan obat yang diberikan.
KTP itu canggih. Cip elektronik yang ada di sana bisa menyimpan berbagai data, bahkan bisa
ditambahkan data baru. Itulah KTP Online yang diperkenalkan pertama kali di Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat, pada 2011. Dari KTP Online ini lantas dikembangkan KTP
elektronik (e-KTP) yang dijadikan program nasional. Jika saja e-KTP berjalan sesuai dengan
rencana, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, orang tak bisa punya
KTP ganda. Data yang tercantum di kartu juga bisa dipangkas. Cukup dengan kolom nama,
tanggal lahir, dan alamat.
Ini bisa menjawab polemik tentang perlu-tidaknya ada kolom agama di KTP, sebuah
perdebatan yang muncul lagi belakangan ini. Adalah Siti Musdah Mulia, guru besar di
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang melontarkan perlunya kolom
agama dihapus dalam KTP. Alasannya, agama kerap dipolitisasi dalam berbagai kepentingan
jangka pendek. Semisal, kata Siti, pegawai yang berbeda agama dengan pimpinannya akan
dipersulit saat naik jabatan. Banyak kasus yang dialami masyarakat minoritas yang tak bisa
mencantumkan agama yang diyakininya karena dipersulit oleh petugas kelurahan dan
kecamatan. Apalagi kalau ada razia yang menyasar masalah SARA.
Di KTP (versi lama) memang sudah ada NIK, lalu kolom nama, tanggal lahir, alamat, agama,
status kawin, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Untuk apa kolom status kawin? Ada kisah
tentang seorang wanita yang ketika memperbarui KTP sedang berstatus janda. Maka petugas
mencantumkan janda di kolom status kawin. Setahun kemudian dia menikah. Tapi, dengan
alasan KTP berlaku lima tahun, dia tak bisa mengubah status itu. Celakanya, saat dia dan
suaminya bermalam di hotel kecil di Pasuruan, ada razia. Suami-istri itu pun terkena razia,
Satpol tak percaya bahwa pasangan itu suami-istri.
Kolom pekerjaan juga tak berguna. Petugas kecamatan yang mengeluarkan "KTP primitif"
itu terbatas pengetahuannya tentang pekerjaan, yakni pegawai negeri, swasta, petani, ibu
rumah tangga, dan pekerjaan lain. Kalau wartawan mencari KTP di kolom pekerjaannya,
tertera swasta atau pekerjaan lain. Adapun kolom kewarganegaraan, untuk apa pula?
Bukankah di balik kolom identitas itu sudah tertulis besar: Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia.
Saatnya program e-KTP yang lebih canggih dari KTP Online versi Purwakarta segera
diteruskan dengan meminimalkan kolom-kolom "KTP primitif". KTP modern sudah
memiliki cip yang bisa dibaca di card reader dan di situ terpampang identitas yang sangat
lengkap. Pada April tahun lalu, PT Jamsostek dan PT Askes juga sudah menandatangani
perjanjian kerja sama pemanfaatan e-KTP dan database kependudukan yang berbasis NIK
dengan Kementerian Dalam Negeri. Kalau e-KTP yang dipermodern ini bisa terwujud,
Pemilu 2019 sudah bisa dilakukan secara e-voting. Betapa murahnya pemilu.
Sayang, program e-KTP terhambat gara-gara korupsi. Mudah-mudahan pemerintahan yang
akan datang serius menggarap KTP modern ini, siapa pun presiden yang terpilih.
Pemerintah Membiarkan Pers Terbelah
Senin, 23 Juni 2014
Sabam Leo Batubara, wartawan senior
Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, fungsi pers adalah mendidik. Mengemukakan persoalan dan menawarkan
pencerahan. Dalam perspektif kebebasan berekspresi sesuai dengan konsep clean and good
governance, tugas media massa adalah membantu mengupayakan well-informed voters.
Sekitar 190 juta pemilih dibantu mendapat pasokan fakta dan kebenaran yang tersedia cukup
dan berimbang tentang rekam jejak para kontestan: partai politik, calon legislator, calon
presiden, dan calon wakil presiden.
Pelaksanaan fungsi dan tugas itu kini bermasalah. Pertama, media dituduh sebagai penyebab
turunnya elektabilitas parpol. Dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta (18/5/2014),
Ketua Umum Partai Demokrat SBY mengemukakan, "Suara Partai Demokrat merosot tajam,
juga karena digempur habis-habisan oleh televisi dan media cetak."
Kedua, pemerintah SBY membiarkan enam stasiun televisi milik penguasa parpol melanggar
perundang-undangan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai dengan kewenangannya,
menjelang hangatnya kampanye pemilihan legislatif, telah merilis penilaiannya bahwa
TVOne, ANTV, RCTI, Global TV, MNCTV, dan Metro TV melanggar peraturan bahwa
program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran
yang bersangkutan dan/atau kelompoknya.
Ketua KPI Judhariksawan, di Jakarta (2/6/2014), menjelaskan bahwa lima media televisi
nasional dinilai tidak netral dalam menyiarkan kegiatan capres-cawapres. TVOne, RCTI,
MNCTV, dan Global TV dinilai memberikan porsi pemberitaan lebih banyak kepada
pasangan Prabowo-Hatta. Metro TV dinilai memberikan porsi pemberitaan lebih banyak
kepada pasangan Jokowi-Kalla.
Ketiga, kampanye hitam yang menyesatkan rakyat dibiarkan. Kini pun kampanye hitam yang
meracuni benak rakyat kita sedang memasuki panggung media massa, utamanya lewat media
sosial. Menurut Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, di Jakarta
(22/52014), sepanjang 2014 terdapat 5.551 pemberitaan yang berkaitan dengan kampanye
jahat. Sebanyak 1.515 ekspose berita kampanye jahat tentang capres Jokowi dan 743
kampanye jahat tentang capres Prabowo. Kampanye jahat didasarkan pada tuduhan tidak
berdasarkan fakta dan merupakan fitnah.
SBY mengharapkan pers mengawal demokrasi. Untuk mengatasi persoalan media
sebagaimana dikemukakan, sebagai sahabat pers, Presiden SBY pun diharapkan mengawal
pers dalam melaksanakan tugasnya mengawal demokrasi. Pertama, kembali memberi contoh
dengan mengadukan pers yang memfitnah ke Dewan Pers. Berita negatif yang terindikasi
beriktikad buruk pun dapat di-KUHP-kan.
Kedua, pemerintah jangan membiarkan media televisi terbelah. Penegakan hukum terhadap
stasiun televisi yang melanggar hukum bukan wewenang KPI atau Bawaslu. Pasal 36 ayat (4)
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebut, "Isi siaran wajib dijaga netralitasnya
dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu." Sementara itu, pasal 55
mengatur, pelanggar pasal di atas dapat berakibat terkena sanksi administratif. Ketentuan
pemberian sanksi berupa denda, penghentian siaran, pembekuan kegiatan siaran, atau
pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran disusun oleh pemerintah. Karena ketentuan
pemberian sanksi sampai sekarang belum juga dibuat oleh pemerintahan SBY, pelanggaran
UU oleh sejumlah media televisi berlanjut terus. Hanya dengan adanya ketentuan pemberian
sanksi, temuan KPI bisa diteruskan ke jalur hukum. Pembiaran tanpa ketentuan pemberian
sanksi oleh pemerintah adalah penyebab pers media televisi terbelah.
Ketiga, penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam mendesak. Kampanye hitam
membodohi dan menipu masyarakat. Presiden SBY sebagai the national policy and decision
maker tidak cukup hanya lewat Twitter berkicau, "Saya tidak menginginkan jika kompetisi
pilpres saling menghancurkan dengan kampanye hitam." Presiden patut menugasi Polri dan
BIN menemukan pelakunya. Dulu Bakin selalu mengetahui ancaman, tantangan, hambatan,
dan gangguan, bahkan sekecil jarum pun yang menerpa negeri ini. Publik perlu tahu
pelakunya, kawan atau lawan, misalnya sisa-sisa G30 SPKI atau Nekolim?
Media sosial yang tidak jelas identitasnya dan sumbernya, dan kegiatannya menyebarkan
dusta, fitnah, dan kebencian, sama saja dengan surat kaleng yang menyebarkan desas-desus
dusta dan fitnah. Menkominfo memblokir media seperti itu tentu saja tidak melanggar HAM.
Sebagai sahabat pers, Presiden SBY perlu bekerja sama dengan pers untuk mengupayakan
media agar tidak terbelah dan membangun demokrasi yang mempersyaratkan kematangan
dan fair play. *
Pasca-Deklarasi Penutupan Dolly
Senin, 23 Juni 2014
Endang Suryadinata, kerap memandu turis Belanda melihat Dolly
Dolly, lokalisasi pekerja seks di Surabaya, ditutup lewat deklarasi di Islamic Center Surabaya
pada 18 Juni 2014. Tapi keesokan hari, para pekerja seks tetap buka, karena tak menerima
deklarasi itu.
Kita tidak tahu apa akhirnya Dolly benar-benar bisa ditutup seperti lokalisasi Kramat
Tunggak di Jakarta atau Saritem di Bandung. Sebab, sudah sering di masa lalu ada wacana
penutupan Dolly. Tapi Dolly tetap buka dan beroperasi sebagaimana biasanya. Mungkin juga
sudah karakter pekerja seks yang harus selalu membuka tubuhnya. Yang terlalu adalah yang
tetap datang kepada pekerja seks, kendati sudah ada deklarasi penutupan.
Dolly memang tak terpisahkan dari sejarah Surabaya. Sebagai fakta historis, Dolly telah
menjadi ikon bagi Surabaya. Tak mengherankan jika, menjelang ditutup, sekitar tujuh media
asing, termasuk dari Belanda, meliput suasana Dolly.
Ketika Belanda masuk lewat Pantai Utara Jawa, sekitar awal abad ke-17 Masehi, muncul
aktivitas pelayanan seksual untuk serdadu, pedagang, dan utusan VOC di sekitar pelabuhan.
Menurut catatan sejarah Kota Surabaya, pada 1864, dari 18 rumah bordil, pelacurnya
berjumlah 228 orang. Dan sejak saat itu, Dolly menjadi ikon khas Surabaya. Menurut data
terbaru per 12 Juni 2014, terdapat 1.444 pekerja seks di Dolly.
Memang, selama kemiskinan masih merajalela, lokalisasi pekerja seks seperti Dolly akan
susah ditutup. Tepat seperti yang ditulis M.A. Muecke dalam esainya yang terkenal, Mother
Sold Food, Daughter Sells Body; The Cultural Continuity of Prostitution (1992). Bahkan, di
kota-kota yang lokalisasinya sudah ditutup seperti Jakarta atau Bandung, justru kian dipenuhi
prostitusi terselubung. Pelacuran jalanan justru kian menggila. Menurut Muecke,
ketidakmampuan keluar dari belitan ekonomi menyebabkan pelacuran sama sekali tidak bisa
dipersepsi sebagai persoalan moralitas. Dalam uraiannya yang satiris, Muecke malah
menyebut prostitusi merupakan pilihan rasional para pelakunya untuk melawan kemiskinan.
Memang secara sosiologis, lokalisasi semacam Dolly merupakan lahan mencari makan,
bukan hanya bagi para pekerja seks dan pemilik wisma, tapi juga bagi para penjual rokok,
kopi, laundry, dan lain-lain. Simak saja militansi warga Dolly yang tergabung dalam Front
Pekerja Lokalisasi dalam menolak rencana penutupan. Mereka memasang ratusan spanduk di
tiap gang. Bahkan mereka menyebut di spanduk bahwa penutupan Dolly merupakan
pelanggaran hak asasi manusia. Juga ada spanduk berbunyi, "Adili pelanggaran HAM di
lokalisasi ini. KPK segera turun tangan atasi korupsi di jajaran Pemkot Surabaya".
Bahkan nama Gus Dur pun disebut di salah satu spanduk. Mereka menyebut "Yes" pada GD,
karena GD membolehkan Dolly tutup hanya selama bulan Ramadan. Sedangkan kepada Gus
Ipul (Saefullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur), mereka menulis "No" karena Gus Ipul
setuju penutupan Dolly selamanya. Mereka juga menulis "Tolak Penutupan Dolly, Harga
Mati".
Memang, menutup Dolly bisa dilakukan. Tapi sejarah membuktikan, prostitusi tak bisa
diberantas. Bahkan, di negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi, yang bercorak teokratis,
prostitusi juga tetap eksis. *
Manusia Perahu
Senin, 23 Juni 2014
Ahmad Sahidah, Dosen Universitas Utara Malaysia
Hanya berselang 12 jam, tragedi perahu karam yang melibatkan penumpang buruh migran
asal Indonesia berulang. Miris! Sementara sebelumnya kejadian ini berlaku di muara Pulau
Carey, perahu serupa karam di 10,5 mil nautika di Tanjung Sepat, Sepang, Selangor. Perahu
tongkang yang membawa 27 penumpang itu tak mampu menahan muatan. Sejauh ini, pihak
berwajib Malaysia menyelamatkan 19 korban dan menemukan 1 mayat.
Bayangkan perahu yang karam sebelumnya! Sebuah tongkang kecil memuat 97 penumpang
di tengah cuaca yang tidak bersahabat. Nelayan lokal saja tidak berani melaut di sekitar
perairan tempat kejadian nahas ini. Berkat kesigapan pihak penyelamat yang melibatkan
pelbagai instansi Malaysia, 61 penumpang bisa diselamatkan, termasuk seorang anak. Tak
pelak, Herman Prayitno, Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, menyatakan penghargaan
bagi negara sahabat atas bantuan tersebut dan sekaligus meminta pihak terkait untuk
menyelidiki penyebab musibah ini.
Lagi-lagi, kelebihan muatan ditengarai sebagai penyebab kapal oleng dan karam. Kapal yang
menuju Tanjung Balai Sumatera itu tak mampu membawa beban yang melebihi kapasitasnya.
Sebagai pengangkut barang, tongkang ini sangat tidak layak untuk penumpang berjumlah 97
orang. Kalaupun bermuatan manusia, kapal berukuran 8 x 2 meter ini hanya bisa menampung
40 orang. Tentu pemilik kapal lebih mementingkan keuntungan dibanding keselamatan
penumpang. Tak ayal, pihak berkuasa memburu yang bersangkutan, termasuk calo atau
tekong yang menjadi orang yang tengah membawa pulang para pahlawan devisa itu ke
kampung halaman.
Untuk kesekian kalinya, buruh migran asal Indonesia meregang nyawa di lautan ketika
mereka ingin "mudik" menyambut puasa dan hari raya. Mereka tak ubahnya manusia perahu
asal Vietnam dulu yang pernah mengarungi lautan untuk menemukan kehidupan baru yang
jauh lebih aman dibanding negara asalnya akibat perang saudara. Cerita pilu tentang mereka
direkam dengan baik oleh Mary Terrell Cargill dan Jade Ngc Quang Hunh dalam Voices of
Vietnamese Boat People: Nineteen Narratives of Escape and Survival. Hari ini, manusia
perahu juga disematkan bagi para pencari suaka dari Timur Tengah dan Asia kecil ke
Australia yang memantik ketegangan antara Negeri Kanguru dan Indonesia.
Ternyata nestapa serupa menimpa saudara kita. Di tengah negeri jiran berusaha untuk
menghentikan perdagangan manusia (human trafficking), pekerja tanpa dokumen itu bisa
lolos dari penyisiran kapal peronda Polisi Laut Malaysia, tapi tak mampu melawan keganasan
alam. Padahal ongkos sekali jalan lebih mahal daripada tiket pesawat, yakni sekitar RM 650,
bahkan salah seorang korban mengaku membayar RM 700-1.200. Tentu, mereka harus
merogoh kantong sekali lagi untuk membeli karcis bus menuju kampung halaman. Mereka
yang selamat tentu tak banyak membawa hasil karena ongkos pulang telah menguras gaji
selama setahun dan mungkin sisa di saku hanya cukup untuk membeli baju baru untuk
keluarga. Lalu, mereka akan kembali menjadi manusia perahu ketika kembali bekerja ke
negeri jiran melalui jalan "tikus". Ini benar-benar tragedi Sisyphus. *
Bahasa, Politik, Fobia
Senin, 23 Juni 2014
Musyafak, Staf Balai Litbang Agama Semarang
Dialek, intonasi, dan gaya berbahasa merupakan representasi politik seseorang. Tuturan
seorang politikus merupakan representasi pandangan atau tindakan politiknya secara umum.
Dalam arena politik berbangsa-bernegara, komunikasi politik hari ini rentan ditautkan dengan
masa lalu, berikut timbunan stigma buruk yang memboncenginya. Mafhum jika sebagian
besar orang Indonesia saat ini merasakan fobia ketika mendengar pidato atau cara bicara
Prabowo Subianto.
Dialek calon presiden dari partai Gerindra itu seolah daur ulang dari gaya tutur Soeharto.
Sebagian orang takut mendengar pidato atau ucapan yang sarat dengan gubahan akhiran "-
ken" ketimbang "-kan". Hingga debat putaran ketiga capres yang telah berlangsung belum
lama ini, publik bisa menyimak Prabowo mengucap "memberesken", "memberiken",
"memerluken", "menyiapken", dan lain-lain. Dialek itu menyeret memori kolektif publik
kepada masa Orde Baru yang sudah ditandai nisan. Tak sedikit orang yang berpandangan
atau memiliki sentimen negatif terhadap Orde Baru merasa takut jika calon pemimpinnya
justru seolah mengajak kembali ke "zaman angker" itu.
Meski belum tentu juga Prabowo hendak membawa Indonesia balik kanan dari agenda
Reformasi untuk kembali ke model kepemimpinan otoritarian Orde Baru, gaya bertuturnya
justru menjadi isyarat bagi publik untuk membaca kehendak politiknya, yang seolah
mengajak mundur ke masa lalu. Sebab, bahasa menyingkapkan ingatan dan fobia tersendiri
bagi publik.
Mochtar Pabottinggi, dalam esainya yang berjudul Bahasa, Politik, dan Otosentrisitas
(dalam Latif dan Ibrahim, 1996), mendedahkan hubungan antara bahasa dan politik yang
begitu erat. Menurut dia, pilihan menggunakan bahasa atau kata-kata tertentu tak lain adalah
berpolitik dalam maknanya yang paling dalam dan luas. Pilihan menggunakan dialek dan
menekankan pengertian tertentu atas kata juga bagian dari berpolitik.
Sementara itu, calon presiden lain, Joko Widodo (Jokowi), relatif bersih dari fobia
kebahasaan semacam itu. Komunikasi politik Jokowi tak terhubung dengan kode-kode
bahasa Orde Baru yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap tak lagi relevan. Ketika
mendengar intonasi, dialek, atau gaya bicara Jokowi, publik tidak memiliki preferensi apa
pun untuk mengaitkannya dengan rezim Soeharto itu. Soal kebahasaan, Jokowi relatif lebih
sedikit menjadi sasaran sentimen negatif dari publik.
Dalam konteks komunikasi politik yang tampak hingga debat putaran ketiga capres, bisa
dikatakan Prabowo tampak lebih unggul dalam hal mengartikulasikan gagasan. Kemantapan
intonasi dan nada bicara Prabowo menjadi nilai plus tersendiri dibanding cara bicara Jokowi
yang kerap tersendat atau terpotong. Sayangnya, gaya tutur Prabowo justru dibebani oleh
dialek "Soehartois" yang menerbitkan sentimen kurang simpatik, bahkan antipatik.
Dialek yang mengujarkan akhiran "-kan" dengan "-ken" merupakan representasi elitisasi
bahasa. Selama puluhan tahun, Soeharto telah meneguhkan identitas dirinya dengan elitisasi
bahasa yang diciptakannya untuk berkomunikasi dengan rakyatnya sendiri. Hari ini, Prabowo
dengan ujaran-ujaran dan bahasa yang digunakannya, setidaknya tampak masih mewarisi
kultur elitisasi bahasa yang diciptakan oleh elite Orde Baru itu. Tanggal 9 Juli memang tak
lama lagi, tapi rasanya Prabowo tetap perlu berintrospeksi dan mengoreksi gaya bertuturnya.
*
Menyelamatkan TNI
Senin, 23 Juni 2014
Buni Yani, Peneliti Universitas Leiden Belanda
Tak ada yang lebih mengkhawatirkan selama pemilihan umum presiden kali ini selain
terbelahnya angkatan bersenjata yang ditengarai konfliknya sudah berlangsung selama
puluhan tahun. Kini muncul kembali pernyataan saling memojokkan dari para purnawirawan
yang seharusnya menjadi panutan bagi para junior mereka.
Kubu TNI "merah-putih" yang mengklaim diri "nasionalis" menghujat kubu TNI "hijau"
yang merasa lebih "islami" secara terang-terangan, dan begitu pula sebaliknya. Hujat-
menghujat ini telah menimbulkan persepsi negatif bagi TNI sebagai institusi.
Bagi masyarakat luas, TNI seharusnya berdiri di atas semua golongan dan tidak berpihak,
tapi yang tertangkap justru sebaliknya. Parahnya, TNI terkesan terbelah dan saling cakar di
dalam. Konflik terbuka ini adalah hubungan kemasyarakatan yang sangat buruk bagi TNI
yang berpotensi membawa pengaruh buruk bagi TNI secara internal dan institusi negara
secara umum.
TNI adalah alat negara yang diberi keistimewaan membawa senjata untuk membela negara.
Masyarakat mulai resah, apa jadinya bila perang kata-kata antar-para purnawirawan ini
merembet ke para prajurit aktif lalu berakhir menjadi perpecahan tidak terkendali yang
melibatkan senjata?
Militer di negara-negara berkembang selalu rentan terlibat atau ditarik-tarik ke ranah politik
yang seharusnya dikuasai oleh politikus sipil. Negara demokrasi adalah negara dengan
supremasi politikus sipil, karena perdebatan di ruang publik adalah perang kata-kata, bukan
perang menggunakan senjata.
Kemenangan dalam negara demokrasi adalah kemenangan argumentasi berdasarkan akal
sehat, bukan kemenangan berdasarkan kekuatan untuk memusnahkan lawan. Prinsip-prinsip
ini menyebabkan militer aktif harus tahu diri dan pintar mengendalikan diri agar tidak terlibat
politik praktis.
Bangsa Indonesia beruntung punya TNI yang dalam sejarahnya tidak pernah melakukan
kudeta. Sikap menahan diri militer Indonesia yang tidak pernah terlibat kudeta sungguh
merupakan prestasi luar biasa di antara negara-negara berkembang yang militernya tak tahan
godaan politik. Seharusnya, prestasi ini juga menjadi patokan dalam memelihara institusi
TNI, agar selalu menjadi kebanggaan anak bangsa.
Namun kecenderungan senior mereka yang sudah purnawirawan selama pilpres ini sungguh
tidak elok, karena telah terjebak menjadi begitu partisan dengan membela capres yang kira-
kira bisa memberikan keuntungan jangka pendek. Bukankah TNI dididik untuk selalu
mengedepankan kepentingan nusa dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan?
Demi menghujat pihak lawan, para purnawirawan ini rela membuka borok TNI secara
telanjang ke muka umum, yang berpotensi merusak citra TNI sebagai kebanggaan bangsa.
Para purnawirawan ini seharusnya berpikir berulang kali sebelum mengeluarkan pernyataan
yang kira-kira bisa berakibat fatal bagi institusi TNI, yang citranya harus dipelihara.
Konflik terbuka antar-purnawirawan ini harus segera diselesaikan sebelum menjadi bencana
yang lebih serius di kemudian hari. Sebagai presiden, SBY sudah seharusnya turun tangan
dan ikut meredakan ketegangan ini demi kepentingan bangsa yang lebih luas. Suara SBY
pasti akan didengarkan, baik oleh para purnawirawan maupun prajurit aktif, apalagi karena
posisi SBY yang juga seorang jenderal purnawirawan. *
Jakarta (Setengah) Baru
24 J uni 2014
Nirwono Joga, Koordinator Gerakan Indonesia Menghijau
Tidak ada sesuatu yang baru dalam perayaan HUT Kota Jakarta ke-487, 22 Juni 2014. Di
balik ingar-bingar penyelenggaraan pesta diskon belanja besar-besaran, festival rakyat, dan
karnaval, Jakarta masih saja belum mampu keluar dari permasalahan laten.
Dalam mengantisipasi banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih bersemangat mengurus
rencana pembangunan tanggul raksasa dan 17 pulau buatan daripada membenahi perbaikan
saluran air, normalisasi kali, revitalisasi waduk dan situ, serta mengatasi kendala pembebasan
lahan dan kepastian relokasi warga ke rumah susun.
Pembenahan lalu lintas juga belum menunjukkan penguraian titik-titik kemacetan. Masalah
korupsi membuat rencana pengadaan bus baru untuk peremajaan bus Transjakarta dan bus
sedang yang sudah tidak laik jalan menjadi tertunda. Sementara itu, pelayanan bus
Transjakarta masih di bawah standar pelayanan minimal.
Pembangunan mass rapid transit (MRT) berkemungkinan besar molor dari jadwal semula,
akibat kurangnya koordinasi antara pelaksana, Pemprov DKI, dan pemerintah pusat. Di lain
pihak, rencana monorel terancam gagal, sudah muncul gagasan pengembangan light rapid
transit (LRT). Perbaikan jalur pejalan kaki dan penyediaan jalur sepeda yang aman dan
nyaman justru tidak termasuk dalam prioritas pengembangan transportasi berkelanjutan.
Perbaikan penataan kawasan melalui program kampung deret cukup mendapat apresiasi dari
masyarakat. Untuk jangka panjang, dalam peremajaan kawasan, Pemprov DKI dapat
mengembangkan kawasan terpadu ramah lingkungan.
Pertumbuhan dan pembangunan kota adalah keniscayaan. Meskipun demikian, tuntutan
ketersediaan tempat tinggal, bangunan pendukung, serta prasarana jalan atau jalur angkutan
umum dapat diarahkan dan dikendalikan. Hal ini diperlukan agar pembangunan Kota Jakarta
tidak melebihi daya dukung lingkungan, sehingga kota tetap berkelanjutan.
Pembangunan Kota Jakarta sudah saatnya menerapkan pembatasan, bahkan pelarangan,
pembangunan fisik horizontal yang boros lahan. Pemerintah kota dapat mengembangkan
kawasan terpadu yang tersebar merata dan terintegrasi dengan jaringan transportasi massal
(bus dan kereta api). Setiap kawasan terpadu minimal terdiri atas satu menara komersial
(sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel) dan hunian vertikal (2-3 menara
apartemen, 3-6 menara rusunawa).
Warga dibatasi memiliki kendaraan pribadi, misalnya, satu unit satu mobil satu ruang parkir,
yang hanya dipakai untuk keluar kota. Untuk kegiatan sehari-hari, warga berjalan kaki atau
bersepeda dalam kawasan, atau menggunakan bus atau kereta api keluar kawasan. Warga
lebih sehat, udara lebih segar, dan iklim mikro lebih sejuk di bawah pepohonan dan taman
kota.
Penegasan perundang-undangan bahwa suatu kota/kawasan perkotaan minimal memliki 30
persen ruang terbuka hijau (RTH) bukan sesuatu yang mengada-ada, apalagi dianggap
menghambat pembangunan kota. Dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, sudah
ditetapkan di mana daerah yang boleh dibangun (ruang terbangun) dan yang tidak boleh
(RTH), yang berfungsi sebagai daerah resapan dan tangkapan air alami.
Kebutuhan air baku dan energi listrik untuk perkotaan diperkirakan semakin meningkat
sejalan dengan laju urbanisasi dan bertambahnya penduduk di perkotaan. Air dipergunakan
untuk irigasi pertanian, industri, dan air bersih warga. Untuk mengantisipasi peningkatan
kebutuhan itu, perlu disiapkan pengembangan pengelolaan air yang ramah lingkungan, serta
pemanfaatan, penerapan, dan pengembangan energi terbarukan.
Untuk membangun ketahanan pangan lokal, perlu dikembangkan pertanian kota yang ramah
lingkungan menerapkan pertanian yang hemat air, tidak boros lahan (pertanian vertikal),
pupuk organik, pembasmi alami dan ramah lingkungan, serta jumlah produksinya berlipat.
Kegiatan industri wajib didukung tempat pengolahan air ramah lingkungan. Budaya hemat air
oleh warga dapat dilakukan dengan kegiatan mengurangi, menggunakan ulang, mendaur
ulang, dan isi ulang.
Konsep pembangunan Kota Jakarta harus diubah secara mendasar, revolusioner, dan visioner.
Keyakinan akan kemajuan kota perlu dijadikan pemikiran utama ketika menata kota. Kota
harus mampu meningkatkan kualitas hidup manusia penghuninya.
Kota didukung perencanaan dan perancangan kota yang berwawasan lingkungan,
berkomitmen menyediakan RTH minimal sebesar 30 persen, dengan pengolahan sampah
ramah lingkungan (kurangi, pakai lagi, daur ulang), pengelolaan air berkelanjutan
(ekodrainase, zero run off), penyediaan transportasi berkelanjutan, pemanfaatan dan
pengembangan energi terbarukan, penerapan bangunan hijau, serta memberdayakan
komunitas hijau.
Kota juga memiliki kemampuan melakukan antisipasi, mitigasi, dan beradaptasi terhadap
perubahan iklim, serta berkembang dengan menggabungkan kemajuan teknologi tepat guna
dan ramah lingkungan dengan potensi dan kearifan lokal. Kolaborasi antara warga,
pemerintah, dunia usaha, dunia luar negeri, dan investor merupakan kunci keberhasilan
pembangunan kota yang layak huni dan berkelanjutan.
Fair Play
Rabu, 25 Juni 2014
Iwel Sastra, komedian, @iwel_mc
Hari-hari ini sepak bola dan politik menarik perhatian masyarakat. Hal ini karena jadwal
Piala Dunia FIFA 2014 bertepatan dengan jadwal kampanye pemilihan Presiden Republik
Indonesia. Saya menemukan beberapa hal menarik terkait dengan politik dan sepak bola,
khususnya di lini massa Twitter pada Minggu, 22 Juni 2014. Saat berlangsung acara debat
calon presiden, lini massa ini dipenuhi kicauan pendukung Prabowo maupun Jokowi. Ketika
memasuki jeda iklan, lini masa mulai dipenuhi kicauan tentang sepak bola. Bahkan ada
kicauan yang berbunyi "anak politik minggir, anak bola mau masuk".
Sepak bola disebut sebagai olahraga dengan jumlah penonton terbanyak di dunia, karena
menonton pertandingan bola memang memiliki kenikmatan tersendiri. Menurut saya,
penyebab utama pertandingan sepak bola itu enak ditonton bukanlah pada kepiawaian para
pemainnya menggiring bola, melainkan karena bola yang digunakan bundar. Menonton
sepak bola tentu tidak akan senikmat sekarang seandainya bola yang digunakan berbentuk
segi empat, apalagi jajaran genjang. Pemain sepak bola tidak akan berani lincah menyundul
bola jika bolanya berbentuk segi empat, karena takut kena bagian yang lancip.
Salah satu yang saya suka dalam menyaksikan pertandingan sepak bola adalah saat pemain
melakukan tendangan bebas. Meskipun Gianfranco Zola, David Beckham, dan Roberto
Carlos telah pensiun sebagai pemain sepak bola, hingga sekarang saya masih terkesan oleh
tendangan bebas yang pernah mereka lakukan saat masih aktif membela klub atau negara
masing-masing. Dalam Piala Dunia 2014 ini, saya terkesan oleh tendangan bebas yang
dilakukan oleh pemain tengah Swiss, Blerim Dzemaili. Bola datar hasil tendangan Dzemaili
menerobos kaki pemain Prancis, kemudian melenggang masuk ke gawang yang dijaga kiper
Hugo LIoris. Meskipun namanya tendangan bebas, tendangan pemain sepak bola profesional
selalu mengarah ke gawang. Berbeda dengan saya yang, saat melakukan tendangan bebas,
tendangannya bebas ke mana-mana.
Sepak bola dan politik memiliki berbagai kesamaan. Dalam sepak bola, setiap klub atau
negara yang bertanding memiliki pendukung. Begitu juga dalam kompetisi politik. Setiap
partai dan kandidat politik memiliki pendukung. Bedanya, dalam politik, terutama dalam
masa kampanye pemilihan presiden saat ini, muncul kampanye hitam yang ditujukan kepada
para capres. Akibatnya, kubu masing-masing capres ini saling tuding mengenai kampanye
hitam yang beredar. Dalam sepak bola, belum pernah saya temukan ada kampanye hitam
menjelang pertandingan. Kalaupun ada kampanye hitam, hal itu tidak akan berpengaruh pada
pertandingan, karena kemenangan dalam sepak bola ditentukan oleh gol terbanyak, bukan
suara terbanyak.
Fair play merupakan semangat yang dijunjung dalam pertandingan sepak bola. Semangat ini
seharusnya bisa diterapkan juga dalam dunia politik, terutama dalam suasana pemilihan
presiden sekarang ini. Dalam semangat fair play, ditanamkan prinsip memenangi
pertandingan dengan cara terhormat serta menerima kekalahan dengan bermartabat. Saya
punya teman yang kalau kalah main sepak bola selalu menerimanya dengan tegar di
lapangan. Kepalanya tetap tegak menerima kekalahan. Ketika sampai di kamar ganti, barulah
ia menangis dalam pelukan teman-temannya. Ini bukan hanya kalah dengan bermartabat, tapi
juga kalah dengan so sweet.*
Survei Abal-abal
Rabu, 25 Juni 2014
Kadir, bekerja di Badan Pusat Statistik
Sejatinya, keberadaan sejumlah lembaga survei (politik) memberi dampak positif terhadap
perpolitikan nasional. Dengan hasil surveinya, lembaga survei dapat menyuguhkan gambaran
konstelasi politik terkini, menyajikan cita rasa kuantitatif (statistik) dalam analisis politik, dan
memprediksi hasil pemilihan legislatif serta pemilihan presiden (pilpres) secara obyektif dan
akurat. Sayangnya, hasil survei politik yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei selama ini
kerap menuai resistansi dan membuat publik bingung.
Resistansi muncul karena hasil survei acap kali tidak akurat, seperti pengalaman pada pemilu
legislatif yang lalu, misalnya. Kala itu, nyaris semua lembaga survei kompak memprediksi
bahwa suara partai-partai Islam bakal anjlok. Faktanya, total suara yang diraih partai-partai
Islam justru mencapai 32 persen. Atas dasar ini, tidak mengherankan bila Ketua Majelis
Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais menyebut hasil survei sejumlah lembaga
abal-abal (Tempo.co, 27 Mei 2014).
Publik juga kerap dibikin bingung karena hasil survei sejumlah lembaga acap kali berbeda
jauh, bahkan saling bertolak belakang. Padahal surveinya menyorot tema yang sama dan
dihelat pada waktu yang nyaris bersamaan. Contoh terbaru adalah hasil survei Lingkaran
Survei Indonesia (LSI) dan Vox Populi Survey (VPS) mengenai elektabilitas dua pasang
calon presiden-calon wakil presiden yang dirilis belum lama ini.
Hasil survei LSI yang dirilis pada 15 Juni lalu menyebutkan, berdasarkan hasil wawancara
terhadap 2.400 responden pada 1-9 Juni, elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta mencapai
38,7 persen, atau terpaut sekitar 6 persen dari elektabilitas pasangan Jokowi-JK, yang
mencapai 45,0 persen.
Sementara itu, hasil survei yang dirilis VPS pada 20 Juni justru menyajikan potret sebaliknya.
Meski dihelat pada rentang waktu yang hampir bersamaan dengan survei LSI, hasil
wawancara terhadap sekitar 5.000 responden pada 3-15 Juni menunjukkan bahwa
elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta mencapai 52,8 persen, jauh mengungguli elektabilitas
pasangan Jokowi-JK yang hanya sebesar 37,7 persen.
Publik tentu bakal bertanya: mana di antara kedua hasil survei tersebut yang benar dalam
menggambarkan preferensi 190 juta pemilih? Repotnya, kedua lembaga menjamin bahwa
survei yang mereka lakukan didasarkan pada metode pemilihan sampel yang sahih dan bisa
diandalkan menurut kaidah statistik. Alhasil, pertanyaan hasil survei mana yang benar
menjadi sulit dijawab.
Memang, hasil survei VPS bisa dibilang lebih "akurat" dibanding hasil survei LSI. Hal ini
tecermin dari batas ambang kesalahan (margin of error) yang lebih kecil dan jumlah sampel
yang lebih banyak. Namun patut dicamkan, akurasi hasil survei juga ditentukan oleh
sejumlah variabel lain.
Selain metodologi pemilihan sampel, kuesioner yang digunakan dan jaminan kualitas (quality
control) selama proses pengumpulan data di lapangan juga mesti didalami. Sayangnya, hal
yang terakhir ini masih gelap. Siapa yang bisa menjamin pelaksanaan survei benar-benar
obyektif dan bersih dari moral hazard?
Karena itu, masyarakat dituntut jeli dalam menyikapi berbagai hasil survei yang dirilis di
ruang publik. Reputasi dan rekam jejak setiap lembaga survei harus dijadikan acuan. *
Politik Praktis Penyelenggara Negara
Rabu, 25 Juni 2014
Reza Syawawi, peneliti hukum dan kebijakan Transparency International - Indonesia
Penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden mulai
memunculkan friksi negatif di antara penyelenggara negara. Masuknya beberapa
penyelenggara negara aktif dalam tim pemenangan calon tertentu, mulai dari bupati/wali
kota/gubernur, menteri, hingga anggota badan negara independen (BPK), telah mengundang
beragam reaksi.
Dalam hal ini, presiden bahkan menyarankan agar penyelenggara negara aktif mengajukan
pengunduran diri sesuai dengan ketentuan. Untuk melihat keterlibatan penyelenggara negara
dalam pilpres, dapat mengkajinya baik dalam perspektif hukum maupun etik (kode etik).
Undang-undang sama sekali tidak mengatur secara spesifik bahwa pejabat negara setingkat
presiden, wakil presiden, menteri, atau kepala daerah masuk dalam tim kampanye resmi yang
didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Frasa dalam undang-undang hanya
menyebutkan tentang "mengikutsertakan" dalam kampanye. Artinya lebih mengarah ke
pelibatan mereka dalam kegiatan kampanye, bukan dalam konteks pencantumannya dalam
tim kampanye resmi.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga tidak diatur mengenai hal
ini, apalagi bagi presiden dan wakil presiden. Sepertinya, undang-undang luput untuk
mengatur hal ini, setidaknya dalam Undang-Undang Pilpres. Padahal pembatasan semacam
ini begitu penting untuk menciptakan prinsip fairness dalam penyelenggaraan pemilu.
Pada sisi lain, undang-undang mencoba membatasi penggunaan kebijakan oleh
penyelenggara negara, termasuk bagi kepala desa. Dalam masa kampanye, pejabat negara,
pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan
lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon.
Selain itu, ada larangan untuk mengadakan kegiatan yang mengarah ke keberpihakan, baik
dalam bentuk pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, maupun pemberian barang kepada
pegawai negeri di lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat yang dilakukan baik
sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye. Larangan ini patut menjadi perhatian
bagi semua pihak, baik pengawas pemilu, penegak hukum, maupun masyarakat. Ada sanksi
pidana penjara dan denda yang bisa dijatuhkan jika pejabat atau penyelenggara negara
melanggar larangan tersebut (Pasal 211-212 UU Pilpres).
Kelemahan pengaturan yang membatasi penggunaan kewenangan pejabat negara dalam
kegiatan politik praktis mesti disiasati dengan mengawasi setiap kebijakan atau tindakan yang
mereka lakukan. Sebab, di situlah potensi penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang akan
menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.
Presiden sebetulnya memiliki kuasa yang lebih besar untuk meminimalkan potensi
penggunaan kewenangan ini untuk kegiatan politik. Namun, sayangnya, presiden sendiri
terjebak dalam dualisme jabatan yang diembannya, baik sebagai pengurus partai politik
maupun sebagai presiden. Maka, agak sulit untuk berharap presiden akan mengambil
tindakan preventif minimal terhadap para pembantunya (menteri) dalam kaitan dengan
potensi terjadinya kejahatan (pidana) pemilu di atas.
Ihwal keterlibatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, dalam
tim pemenangan calon tertentu ini juga luput dari pengaturan dalam Undang-Undang Pilpres.
Undang-undang hanya memberikan larangan bagi pelaksana kampanye untuk
mengikutsertakan anggota BPK dalam kegiatan kampanye.
Perbuatan ini dapat menjerat pelaksana kampanye dan anggota BPK sebagai pelaku kejahatan
atau pidana pemilu yang diancam pidana penjara dan denda (pasal 216 - 217 UU Pilpres).
Tetapi pengaturan ini memiliki kelemahan mendasar, bahwa perbuatan ini hanya berlaku
dalam kegiatan kampanye. Tidak ada larangan jika itu dilakukan baik sebelum maupun
sesudah masa kampanye. Padahal ini justru diberlakukan terhadap penyelenggara atau
pejabat negara yang lain (Pasal 44 UU Pilpres).
Jika sanksi pidana tidak dimungkinkan karena tak diatur dalam Undang-Undang Pilpres,
sanksi etik masih terbuka lebar mengingat perbuatan ini telah mendegradasi keberadaan BPK
sebagai lembaga negara yang independen. Ada ketentuan etik yang dilanggar karena terlibat
secara langsung dalam kegiatan politik praktis.
Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK pada pasal 6 ayat (2)
huruf (a), anggota BPK dilarang menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-
kegiatan politik praktis. Maka, berdasarkan hal ini, tidak ada alasan bagi Majelis Kehormatan
Kode Etik BPK untuk tidak menyidangkan yang bersangkutan karena diduga telah melanggar
kode etik.
Ke depan, sebaiknya ada pengaturan yang lebih komprehensif untuk mengatur seluruh
penyelenggara negara dalam kegiatan politik praktis. Sanksi pidana dan etik perlu
diberlakukan agar potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik bisa
diminimalkan. *
Prostitusi
Rabu, 25 Juni 2014
Heri Priyatmoko, Alumnus Pascasarjana Sejarah FIB UGM
Siapa sangka bahwa Dolly, tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu, akhirnya ditutup.
Dolly merupakan kawasan "hitam" yang mampu bertahan lama, bahkan jauh lebih berkibar
dibanding Kramat Tunggak (Jakarta), Jempingan (Sukoharjo), dan Silir (Kota Solo) yang
lebih dulu dilenyapkan. Prostitusi alias pelacuran ialah penyerahan diri seorang wanita
kepada banyak laki-laki dalam hubungan seksual dengan pembayaran tertentu. Dalam
praktek itu, lahir istilah pelacur, "wanita publik", sundel, wong wedok nakal, lonthe,
pelayahan, perempuan jalang, atau diperhalus bahasanya menjadi wanita tunasusila.
Terdapat pula singkatan khas Jawa yang sarat humor, seperti minakjinggo, yang punya
kepanjangan miring penak, jengking monggo (miring rasanya enak, nungging juga silakan).
Di ruang jasa bisnis seks ini juga muncul pantun lokal yang tampaknya lahir secara spontan.
Semisal, kecipir manuk trucukan, monggo mampir thuthuk-thuthukan. Lebih jauh lagi,
komunitas penghuni lokalisasi ini rupanya memiliki bahasa atau idiom khas yang sulit
dipahami oleh khalayak. Sekadar contoh, dibayar "dua mawar", artinya dua lembar seratus
ribu rupiah.
Bukan cuma pemerintah Republik Indonesia yang kerepotan memberantas aksi pelacuran dan
menutup lokalisasi. Tempo doeloe, pemerintah kolonial Belanda pernah dibikin pusing oleh
praktek para penjaja cinta yang merajalela. Terkisah, pada 1852, pembesar Belanda
menelurkan regulasi yang merestui komersialisasi aktivitas seksual, menimbang banyak
prajurit yang tak membawa istri ke Hindia-Belanda. Lalu, dibuatlah rumah bordil. Dan, hal
ini mengundang masalah baru.
Dalam kumpulan dokumen resmi Belanda yang berjudul Pemberantasan Prostitusi di
Indonesia Masa Kolonial, diketahui bahwa aneka cara ditempuh demi mengawasi kegiatan
prostitusi di rumah bordil gara-gara meluasnya wabah penyakit kelamin, yakni syphilis. Kala
itu, tingkat penularan infeksi penyakit kelamin sangat tinggi.
Dikabarkan bahwa dalam waktu singkat di rumah sakit militer sudah ada 40 orang yang
dirawat. Sebagian dari mereka menderita syphilis dan penyakit kelamin lainnya. Ini bisa
dibaca dari data mengenai anggota militer yang terserang penyakit akibat "maen" di rumah
bordil mulai 1870 hingga 1890. Pada era 1870 tercatat 575 orang menderita syphilis dan
5.105 orang terkena morbi veneris. Pada 1882, jumlah penderita syphilis membengkak
menjadi 1.290 orang. Sedangkan morbi veneris terparah terjadi pada 1887, yaitu 10.108
orang. Usaha pengobatan secara medis tidak berbuah manis.
Sebetulnya, pada 1874, toewan kulit putih telah mengkodifikasi kebijakan isolasi bagi para
perempuan nakal yang ketahuan mengidap penyakit kelamin. Mereka dikarantina dalam
suatu "rumah bagi perempuan sakit" dengan pengawasan tenaga medis. Selepas bisa
membuktikan dirinya sehat, mereka akan dikeluarkan.
Demikianlah, masalah prostitusi senantiasa mengikuti gerak zaman. Prostitusi memang
bukanlah sebatas urusan perut. Sampai kapan pun, akar prostitusi tampaknya sulit dicabut
jika pendidikan bagi kaum wanita masih rendah. Juga tipisnya pemahaman mereka terhadap
aktivitas prostitusi, bahwa praktek ini berdampak negatif, misalnya penyebaran penyakit
kelamin (HIV/AIDS) yang menuai kematian. Prostitusi ialah anak zaman yang dianggap
haram, namun selalu dibutuhkan. *
Muhammadiyah dan Pemilihan Presiden
Rabu, 25 Juni 2014
Benni Setiawan, Dosen Universitas Negeri Yogyakarta
Pemilihan presiden 9 Juli sudah semakin dekat. Black campaign (kampanye hitam) muncul
bertubi-tubi. Bahkan, Muhammadiyah, sebagai organisasi massa Islam, pun ikut terseret
sebagai korban dalam arus kampanye hitam ini. Hal itu menunjukkan secara gamblang bahwa
kebangsaan kita semakin pudar dan rapuh. Kebangsaan kita jauh dari semangat Pancasila dan
UUD 1945.
Sebagai organisasi yang lebih tua dari umur Republik, Muhammadiyah terpanggil untuk
menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam pidato milad Muhammadiyah ke-101, tertulis,
"Muhammadiyah mengajak pemerintah di seluruh tingkatan untuk semakin meningkatkan
komitmen dan kesungguhan dalam memajukan bangsa, disertai dengan sikap mengedepankan
keadilan dan kejujuran, berdiri di atas semua golongan, tidak partisan, bermitra dengan
seluruh komponen bangsa, dan mampu menunjukkan jiwa kenegarawanan yang utama."
Pidato tersebut menegaskan posisi dan peran Muhammadiyah dalam kebangsaan.
Muhammadiyah, sebagai bagian dari civil society, perlu mengingatkan calon presiden.
Bahwasanya mereka dipilih untuk menjadi pemimpin. Pemimpin adalah mereka yang
senantiasa merasa gelisah jika tidak mampu bekerja optimal. Senantiasa menjaga lisan dan
perbuatan guna memakmurkan bangsa, dan senantiasa ingin berbuat kebajikan setiap saat.
Karena itu, seorang pemimpin selayaknya menyemai kebajikan setiap saat. Dalam
kesejarahan, Muhammadiyah telah mewariskan semangat juang menjadi pelayan dari
kepemimpinan A.R. Fachruddin. Pak AR, begitu ia disapa, menjadi simbol dai ikhlas,
bersahaja, dan tawaduk.
Ia pun senantiasa menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui bahasa-bahasa sederhana.
Ia senantiasa ingin dekat dengan umat. Ia sering mengunjungi desa dan menyapa masyarakat.
Kesederhanaan, ketulusan, dan ketelatenan menyapa masyarakat menjadi ciri utama
kepemimpinan Pak AR. Melalui sikap yang demikian, Presiden Soeharto pun seakan tunduk
pada wejangan Pak AR.
Lebih lanjut, kebangsaan hari ini akan kokoh jika pemimpinnya mampu menjadi teladan.
Sebaliknya, ketika keteladanan menghilang dan hanya menjadi kata tanpa ucapan,
kebangsaan akan runtuh. Bangsa ini harus diselamatkan dari proses kepemimpinan yang
rapuh. Pasalnya, jika bangsa dan negara ini ambruk, Muhammadiyah pun akan roboh.
Karena itu, Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung atau menolak seorang capres.
Sikap itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah dalam pemilihan presiden 2014 ingin
membangun politik berperadaban. Politik adiluhung sebagai pengejawantahan sikap dan
konsistensi Muhammadiyah dalam membangun kebangsaan.
Kelompok-kelompok seperti Surya Madani Indonesia (SMI) yang mendukung pasangan
Prabowo-Hatta dan Relawan Mentari Indonesia (RMI) yang mendukung pasangan Jokowi-
JK, tidak bertindak atas nama Muhammadiyah. Mereka adalah simpatisan yang kebetulan
terbangun dari jejaring aktivis Persyarikatan. Jadi, tak ada hubungan struktural dengan
Persyarikatan.
Muhammadiyah memposisikan diri sebagai bapak bangsa, pengayom semua capres. Sikap ini
bukan cara Muhammadiyah mencari selamat atau bermain di dua kaki. Muhammadiyah
tetaplah organisasi besar yang tak tergiur bermain di arena politik. Khitah sebagai organisasi
massa Islam amar makruf nahi mungkar lebih berharga daripada sekadar turut serta dalam
hiruk-pikuk politik. *
Dipenjara Seumur Hidup
Rabu, 25 Juni 2014
Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM
Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa Akil Mochtar
hukuman penjara seumur hidup. "Menjatuhkan pidana seumur hidup ditambah dengan pidana
denda Rp 10 miliar dan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam
pemilihan umum yang ditentukan menurut aturan umum," kata jaksa Pulung Rinandoro di
Pengadilan Tipikor Jakarta (Koran Tempo, 17 Juni 2014).
Dari banyaknya catatan kasus korupsi, sepertinya baru kali ini jaksa melayangkan tuntutan
seumur hidup terhadap seorang terdakwa. Dari unsur penegak hukum, pernah ada mantan
jaksa Urip Tri Gunawan yang dituntut hukuman 15 tahun penjara. Seorang mantan Inspektur
Jenderal Djoko Susilo lebih tinggi tiga tahun tuntutannya, yakni 18 tahun. Tak sampai angka
pidana penjara maksimal 20 tahun.
Untuk menuntut pesakitan dengan ancaman penjara seumur hidup? Belum ada, sampai korps
Adhyaksa melakukannya terhadap mantan Ketua Hakim Konstitusi. Waktu serasa benar-
benar berhenti bagi Akil. Dinginnya bui mulai menggelayut di hadapannya.
Ancaman pidana seumur hidup bukanlah stelsel baru dalam undang-undang pemberantasan
korupsi. Dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 setidaknya ditemukan empat
ketentuan ancaman penjara seumur hidup, yakni dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal
12B. Meski disebutkan, bunyi keempat pasal tersebut menyuratkan sifat alternatif, bukan
kumulatif. Penjara seumur hidup adalah sebuah pilihan ancaman, bukan keharusan.
Ada faktor yang mempengaruhi jaksa menjatuhkan pilihan ancaman. Selain rumusan delik
yang harus dipenuhi, kondisi di luar hukum, semisal sosial, politik, atau ekonomi, bisa
menjadi alasan dasar (basic reason) dalam menyepakati pasal mana yang akan diancamkan
terhadap terdakwa. Tengok saja begini, sebagian bunyi Pasal 12 huruf c Undang-Undang
Pemberantasan Korupsi adalah "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta
dan paling banyak Rp 1 miliar... c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi
putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili."
Kenapa penjara seumur hidup-berdasarkan rumusan Pasal 12 huruf c-diancamkan kepada
oknum hakim korup? Kenapa bukan pidana 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar saja yang
dipilih? Faktor di luar hukum positif turut andil dalam pengambilan keputusan ini. Pertama,
faktor sosial. Hakim, sebagaimana banyak orang paham, adalah wakil Tuhan di bumi.
Khalayak menyerahkan perkaranya untuk diadili kepada wakil Tuhan. Lalu, usut punya usut,
hakimnya ternyata korup. Maka si hakim ini melakukan dua kebohongan dalam waktu
bersamaan. Membohongi para pencari keadilan (justicianabelen) dan membohongi pemberi
mandat, yakni Tuhan, sehingga apa hukuman yang pantas untuk hakim yang korup kalau
bukan penjara seumur hidup?
Kedua, faktor politik ketatanegaraan juga bisa mempengaruhi jaksa dalam memilih ancaman
pidana penjara seumur hidup. Dalam kasus Akil Mochtar, faktor politik ketatanegaraan ini
bentuknya lebih spesifik. Negara dan rakyat mempercayakan posisi kursi utama kepada Akil
sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Tapi, ia
malah mengkhianati posisi tersebut. Akibatnya, sempat keadaan negara tidak stabil karena
pilar kekuasaan kehakiman goyah. Ketua MK ditangkap karena korupsi. Kepercayaan
terhadap kekuasaan kehakiman, lambat tapi teratur, turun ke titik nadir, sehingga apa
hukuman yang pantas kalau bukan penjara seumur hidup?
Ketiga, faktor pengkhianatan terhadap harapan publik. Pengkhianatan paling besar
sebenarnya dilakukan kepada optimisme rakyat dalam melawan korupsi. Waktu itu, MK
dianggap satu-satunya lembaga yang bersih dan tidak terkontaminasi perilaku jahat setelah
KPK dirundung masalah pidana karena Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, terjerat kasus
pembunuhan. Ekspektasi publik terhadap KPK menurun. Tinggal MK jadi tumpuan. Prof
Jimly Ashiddiqie, Ketua MK pertama, dinilai berhasil menjaga institusinya. Mahfud Md.,
Ketua MK berikutnya, melanjutkan keberhasilan ini. Paling tidak, ketua MK tak korupsi.
Giliran Akil Mochtar, korupsi bebas (atau sengaja dibuat bebas?) masuk ke MK. Optimisme
publik dibunuh. Pesimisme muncul seperti cendawan: tak ada lagi lembaga yang bebas dari
korupsi, sehingga apa hukuman yang pantas untuk orang nomor satu di kekuasaan yudisial
yang diduga korup dan mematikan optimisme publik kalau bukan penjara seumur hidup?
Tak ada yang perlu dirisaukan dengan ancaman penjara seumur hidup. Hukum positif jauh-
jauh hari sudah memasukkan ketentuan demikian. Cuma jaksa tak sering memanfaatkannya.
Sebab, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, selain sifat ancamannya yang
alternatif itu. Sekarang jaksa mulai berani, dan akan terbiasa menggunakannya. Pesannya
hanya satu, korupsi, dalam wujud apa pun, menjadi penyakit yang menggerogoti rakyat dan
negara. Maka harus dilawan dengan peranti yang maksimal: penjara seumur hidup... *
Menggadang Suara Tionghoa
Jum'at, 27 Juni 2014
Christine Susanna Tjhin, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for
Strategic and International Studies (CSIS)
Setelah acara temu muka capres dengan sebuah asosiasi Tionghoa di Jakarta, minggu lalu,
sejumlah media mengisyaratkan gemuruh dukungan Tionghoa untuk Prabowo. Bau amis
rasisme pun sempat merebak di media sosial. Tionghoa dituduh oportunis politik dan
memanfaatkan uang untuk membeli pengaruh.
Faktanya, komunitas Tionghoa itu heterogen. Klasifikasi totok dan peranakan sudah lama
tidak laik, apalagi dikotomi simplistik Tionghoa kaya pro-Prabowo atau Tionghoa miskin
pro-Jokowi. Tulisan ini tidak berpretensi meramal akan ke mana suara Tionghoa dalam
Pilpres nanti, karena bukan itu esensi partisipasi politik Tionghoa.
Peningkatan partisipasi politik Tionghoa sejak reformasi patut dihargai. Di tataran hukum,
peraturan diskriminatif warisan Orde Baru hampir semua dipreteli. Di tataran sosial politik,
perjuangan masih ruwet. Trauma Mei 1998 masih merupakan momok terbesar. Sejumlah
kelompok kepentingan mendaur ulang trauma ini demi kepentingan Pilpres nanti.
Munculnya Babinsa di wilayah mayoritas Tionghoa kemarin adalah kasus terbaru. Beruntung
TNI sigap merespons. Hal itu tidak seburuk tingkah sejumlah tokoh Tionghoa yang gegabah
berkoar di media, mengklaim mewakili masyarakat Tionghoa dalam mendukung capres
tertentu. Siapa pun dari pihak mana pun yang seenaknya mengklaim mampu atau menuduh
yang lain menggiring suara Tionghoa ke kubu mana pun, itu hanya sedang menipu orang lain
dan dirinya sendiri. Ironisnya, dagangan dungu itu masih laku.
Banyak yang menepis suara Tionghoa karena, menurut Sensus 2010 (yang akurasinya
dipertanyakan), populasinya tidak mencapai 1,2 persen. Banyak yang mengincar kontribusi
Tionghoa sebatas fulus. Tapi demokrasi bukan monopoli mayoritas dan bukan dagangan.
Kekuatan partisipasi politik Tionghoa ada pada kemampuan mengarus-utamakan "masalah
Cina" ke dalam kerangka tantangan keberagaman Indonesia. Pengawalan proses legislasi
RUU Kewarganegaraan dulu merupakan kisah menarik, di mana komunitas Tionghoa,
dengan keterbatasannya, beraliansi dengan beragam komunitas demi mengarus-utamakan
kasus SBKRI ke dalam kerangka perlindungan warga negara.
Isu hangat seputar Pilpres 2014 adalah "Prabowo: Dalang atau Kambing Hitam Mei 1998?".
Enam belas tahun tanpa penyelesaian hukum membuat spekulasi meradang. Ketimbang
menggunakan proses hukum dalam mencari kebenaran, para politikus memilih proses politik
yang manipulatif, intimidatif, dan temporer (saat pemilu saja) untuk menggaet suara
Tionghoa. Ada sekelompok kecil Tionghoa yang ingin lupa-entah takut, lelah, atau tengik
dan haus kekuasaan.
Pemerintahan SBY menganggap Keppres Nomor 12/2014 sudah cukup untuk Tionghoa,
ketimbang membentuk Pengadilan HAM. Keppres itu hanya menggaruk permukaan
"Masalah Cina" saja. Selain miskin sosialisasi dan hanya mengatur institusi pemerintah,
konsistensi dan efektivitasnya masih tanda tanya. Keppres ini salah kaprah dan relatif
diabaikan publik. Bandingkan dengan pembentukan Pengadilan HAM yang bisa memberikan
keadilan bagi korban Mei 1998 (baik Tionghoa maupun bukan), dan menjamin teror negara
serupa tak kan terulang.
Kubu Prabowo menggadang Ahok sebagai bukti kalau Prabowo tidak "anti-Cina". Tapi ada
anggapan kalau itu hanya simbolis, karena mangkirnya Prabowo dari panggilan Komnas
HAM pada 2006 jelas tidak membantu proses penyelesaian hukum. Terlebih, manifesto
Gerindra justru menolak Pengadilan HAM.
Kubu Jokowi juga terciprat isu Mei 1998 ini dengan sosok Wiranto. Memang Prabowo
sebagai capres mendapat sorotan, tapi ini juga catatan penting buat kubu Jokowi. Siapa pun
yang menang, tuntutan keadilan akan terus dikumandangkan. Entah itu isu pengadilan HAM
atau lainnya, pengarus-utamaan partisipasi politik Tionghoa diuji dalam Pilpres 2014, karena
kampanye hitam bernuansa rasis dan intimidatif ala Orba begitu gencar. Tapi tidak ada alasan
bagi masyarakat Tionghoa untuk bersembunyi di bawah ketiak ketakutan, karena 2014 bukan
1998.
Telah muncul generasi baru Tionghoa yang tak lagi kikuk bersuara. Eksistensi trauma Mei
1998 diimbangi gerakan melawan lupa yang melibas pagar etnisitas. Paling tidak, mereka
sudah lebih sadar akan keterkaitan alamiah kasus diskriminasi Tionghoa dengan manajemen
pluralisme Indonesia.
Kedua kubu capres merangkul politisi Tionghoa dengan beragam karakter dan gaya. Jika
tidak bisa sigap mengikuti arah arus utama dan peka terhadap situasi akar rumput, partisipasi
itu bukan hanya ibarat masturbasi politik yang menjustifikasi stereotip Tionghoa, tapi juga
akan menyiram bensin di atas bara politik identitas.
Terlebih mengingat mencuatnya Tiongkok sebagai adidaya baru masih diwarnai perdebatan
apa Tiongkok adalah ancaman atau mitra sejati. Jangan lupa, sepanjang sejarah, suka atau
tidak, dinamika Tionghoa tidak pernah dilepaskan dari dinamika Tiongkok. Maka dari itu, ini
imbauan untuk semua pihak-Tionghoa atau bukan-hati-hati menggadang suara Tionghoa.
Nyadran dan Kohesi Sosial
Jum'at, 27 Juni 2014
Aris Setiawan, Pengajar di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta
Poerwardarminto (1937) mengartikan nyadran sebagai ritual menziarahi makam leluhur yang
waktunya telah ditentukan. Nyadran biasanya dilangsungkan secara kolektif menjelang bulan
puasa atau Ramadan. Aktivitas ini bukan semata ungkapan ekspresi religius masyarakat
Jawa, tapi juga kultural. Tradisi ini menjadi simbol yang mempertautkan masyarakat Jawa
dengan leluhur atau nenek moyangnya. Di wilayah itu, orang Jawa menyadari bahwa dirinya
memiliki garis keturunan, tidak lahir secara tiba-tiba. Karena itu, mereka dituntut untuk
berbakti, menghargai jasa para leluhur dengan berkirim doa. Hubungan kekerabatan tidak
putus walaupun ajal telah menjemput.
Ritual nyadran biasanya diisi dengan aktivitas membersihkan makam, selamatan atau
kenduri, membuat kue apem dan ketan. Di sisi lain, nyadran juga menjadi sarana
implementasi terbentuknya kohesi sosial masyarakat Jawa.
Nyadran adalah wujud pengorbanan masyarakat Jawa dalam mempertahankan nilai-nilai
tradisi. Bahkan aktivitas menziarahi makam juga dilakukan oleh banyak pemimpin negeri ini.
Sukarno dan Soeharto dianggap sebagai presiden yang tekun menziarahi makam-makam
Jawa yang dianggap keramat. Hal itu juga masih ditiru hingga sekarang, lihatlah calon
presiden kita yang melakukan aktivitas serupa. Prabowo nyekar di makam Soeharto dan
Sukarno, begitupun Jokowi yang ke makam Gus Dur dan ayahnya.
Bagi orang Jawa, makam tidak dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir, melainkan
terminal yang menghubungkan manusia dengan dunia lain, fana dan gaib. Karena itu,
"terminal" tersebut haruslah dirawat dan dibersihkan. Semakin indah makam atau kuburan,
menunjukkan bahwa mereka merawat masa lalu dengan mengenang leluhur, dan menghargai
masa depan melalui doa dan pengharapan. Nyadran datang lewat akulturasi yang harmonis
antara Islam dan Jawa. Nyadran adalah cara orang Jawa dalam memahami esensi Islam.
Layaknya mendengarkan gamelan Sekaten di masjid Agung dan menonton pertunjukan
wayang kulit dengan lakon Dewa Ruci.
Nyadran menghasilkan tata hubungan yang vertikal dan horizontal; meningkatkan hubungan
dengan Tuhan dan sesama manusia. Lewat aktivitas nyadran, manusia Jawa saling
berkumpul bersama tanpa adanya sekat atau kelas-kelas sosial. Ritual nyadran menarasikan
bagaimana kebudayaan Jawa dibangun atas persamaan, tidak berdasarkan perbedaan. Setelah
ritus itu dilangsungkan, kehidupan dilangsungkan dengan semangat dan cita-cita baru.
Berharap pada masa kini dan yang akan datang menjadi lebih baik.
Nyadran kemudian tak lebih dari usaha orang Jawa dalam memotivasi diri. Mereka bukannya
menggantungkan segala sesuatu pada doa, melainkan diimbangi usaha dengan membangun
jaringan lewat pertemuan sosial di ritual ini. Karena itu, pelbagai kesepakatan, kerja sama,
solusi masalah, dan saling membantu dilahirkan kala pertemuan sosial dilangsungkan.
Nyadran mengakomodasi segala kemungkinan tersebut. Pada bulan ini, menjelang Ramadan,
nyadran mengingatkan kita tentang arti penting saling mengasihi dan menyayangi sesama
demi kerukunan hidup. Di mana hal tersebut semakin sulit dijumpai dan menjadi peristiwa
yang langka. *
Janda
Jum'at, 27 Juni 2014
Purnawan Andra, Penulis
Beberapa waktu lalu, Komunitas Janda Indonesia (Kojaindo) mendeklarasikan dukungan
untuk calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla di Bandung (4 Juni 2014).
Harapannya, jika terpilih, keduanya dapat lebih memperhatikan dan memperjuangkan kaum
perempuan, terutama para janda yang berjuang sendiri tanpa ada dukungan suami. Komunitas
ini juga bermaksud menghilangkan konotasi janda yang selama ini dinilai negatif
(Liputan6.com).
Menarik mencermati penyebutan janda dalam niatan ini dalam hajatan politik bangsa nanti.
Apakah kumpulan janda tersebut akan menjadi suatu kekuatan politik yang menambah suara
bagi kubu calonnya?
Penyebutan janda menjadi wacana yang mengusik perhatian. Janda adalah status perempuan
yang sudah tidak bersuami, entah karena perceraian atau kematian suami. Status ini kerap
menciptakan persepsi dan tendensi tertentu dalam konstruksi sosial masyarakat. Muncul
pelbagai idiom lanjutan yang mengandung bermacam maksud definitif terkait dengan status
janda, seperti janda kembang, janda muda, atau randa kempling.
Bandung Mawardi (2009) mensinyalir selama ini sebutan janda "difasilitasi" di acara-acara
gosip. Acara infotainmen menjadi rumus mujarab untuk menciptakan isu mengenai para artis
yang menjanda, akan menjadi janda ataupun tidak lagi menjanda. Perceraian para artis
menjadi isu penting, dan para pelakunya dikenai sebutan janda dalam berbagai nada persepsi:
ada yang sumbang, simpati, sedih, atau menghujat. Publik terlibat secara emosional terhadap
para artis yang menjanda. Infotainmen juga menampilkan efek janda bagi para artis. Ada
yang tampak lega dan memancarkan spirit untuk menata hidup tanpa suami. Ada yang
tampak memelas dengan konstruksi diri sebagai korban atau pihak terkalahkan. Media
mengolah wacana janda menjadi lakon menggemaskan dan mengenaskan. Pengarahan pada
tendensi-tendensi tertentu menjadi permainan otoritas untuk membuat publik mendukung.
Wacana tentang janda di(re)produksi dalam sistem pemaknaan kontemporer.
Sejak awal, identitas perempuan memang selalu terbelah. Rohima (2010) menjelaskan bahwa
lingkungan telah memilihkan nama untuk perempuan. Ketika pulang ke rumah, perempuan
telah menjadi ibunya si A, B, C, sampai Z anak-anaknya. Di lingkungan terdekat rumahnya
pun, perempuan akan lebih dikenal sebagai bu Nama Suaminya, bukan bu Namanya Sendiri.
Perempuan tidak ikut menamai diri sendiri di dalam pertumbuhan dan perkembangan
kehidupannya, serta tidak menamai dunia di sekitarnya.
Perempuan harus menegosiasikan kuasa masyarakat yang didasarkan pada agama, pasar, dan
politik. Perempuan di Indonesia ditarik dalam dua arah: di satu sisi mereka ditarik pada
peranan yang diterapkan kepada mereka oleh lingkungan sosial, keluarga, biologi (peran
yang digariskan sebagai ibu dan istri), dan seksualitasnya (kekuatan mereka untuk menggoda
laki-laki), termasuk peranan perempuan sebagai pelestari tradisi, moralitas, dan identitas
nasional. Di sisi lain, mereka ditarik meneruskan kehidupan kreatif pribadinya (Lindsay,
2009: 15).
Wacana mengenai perempuan (apalagi janda) direproduksi dalam pelbagai konteks, tanpa
batas. Masyarakat perlu memaknai ulang wacana janda secara lebih proporsional,
kontekstual, dan tidak reaksioner. Peranan perempuan perlu direpresentasikan sebagai ruang
pembacaan yang lebih kritis tentang dinamika sosial, modernitas, dan identitas Indonesia itu
sendiri. *
Ramadan dan Oase Politik
Sabtu, 28 Juni 2014
Munawir Aziz, Peneliti
Di tengah terik panas kontestasi politik menjelang Pilpres 2014, umat Islam Indonesia
disuguhi oase bernama Ramadan. Bulan keberkahan bagi umat seluruh alam ini seakan
menjadi penyegar di tengah deru kampanye dan pertarungan kepentingan antarkelompok.
Ramadan menjadi bulan ujian, sekaligus sebagai ruang pembuktian. Di tengah oase
Ramadan, warga Indonesia akan menyelenggarakan hajatan politik yang menentukan nasib
bangsa, yakni pemilihan presiden 9 Juli mendatang.
Tentu saja, Ramadan kali ini sangat menarik karena menjadi kawah ujian bagi warga negeri
ini, yang sedang berebut benar dan mengklaim tegar. Ramadan kali ini sejatinya bukan hanya
milik warga muslim semata, tapi juga milik semua. Ujian-ujian kesabaran, ketabahan, dan
prinsip menahan diri menjadi bagian utama untuk membentuk pribadi pilihan. Inilah saat
yang tepat untuk membuktikan diri sebagai pribadi yang bermanfaat: berbagi pada sesama,
menghentikan kampanye hitam, dan menyebarkan kebaikan.
Bulan Ramadan memiliki banyak nama: syahrul qur'an (bulan Al-Quran diturunkan), syahrul
rahmah (bulan pelimpahan rahmat), syahrul najah (bulan keberuntungan), syahrul juyud
(bulan kedermawanan), syahrul shabri (bulan kesabaran), syahrul tilawah (bulan
memperbanyak membaca Al-Quran), dan syahrul shiyam (bulan berpuasa). Nama-nama yang
melekat pada Ramadan ini membuktikan pentingnya bulan ini bagi keseimbangan alam
semesta. Kali ini, Ramadan juga bisa dimaknai sebagai syahrus siyasah (bulan politik).
Terang saja, politik yang menjadi misi bersama adalah politik kebangsaan dan kerakyatan,
bukan semata politik praktis yang memperjuangkan kepentingan pribadi ataupun kelompok.
Visi politik yang mengejawantahkan ide-ide kebaikan dan mendukung kepemimpinan yang
kuat dan bermoral sedang dibutuhkan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang amanah,
tegas, dan mampu melindungi sekaligus menerjemahkan aspirasi rakyat dalam kebijakan
pemerintahan. Negeri ini bukan sekadar membutuhkan politikus yang mengaku sebagai
pemimpin, tapi juga menanti seorang pemimpin yang dapat membawa bangsa ini ke arah
yang lebih baik.
Pada hari-hari menjelang pilpres kali ini, semakin sering terlempar kebencian, egoisme, dan
klaim kebenaran sepihak. Kampanye yang dilakukan oleh tim sukses ataupun relawan
sejatinya mencerminkan kepribadian politik yang sesungguhnya. Mereka yang menyebar
kebaikan dan visi-misi kesejahteraan merefleksikan pola kepemimpinan yang bermartabat.
Marwah politik pemimpin tidak saja ditentukan oleh tujuan politiknya, tapi juga strateginya.
Jika yang ditunjukkan hanya kejelekan dan kekejian, yang melekat dalam inti kepemimpinan
hanyalah egoisme dan nafsu kekuasaan.
Ramadan menjadi ruang refleksi bersama tentang bagaimana menahan diri dari nafsu-nafsu
kekuasaan. Ramadan adalah momentum mengendapkan amarah, menjernihkan batin, dan
mentransformasi kebaikan. Memaknai Ramadan sebagai gerbang menjemput kebaikan,
menjadi krusial di tengah lautan fitnah dan kampanye hitam yang riuh menjelang pemilihan
presiden. Ramadan adalah bulan berkah. Maka, selayaknya ia dihayati dengan sepenuh hati:
dengan cara-cara yang baik untuk tujuan yang baik. *
Efektivitas Debat Calon Presiden
Sabtu, 28 Juni 2014
Agus Sudibyo, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia
Sebagai gagasan yang relatif baru dalam sistem pemilu di Indonesia, acara debat capres patut
disambut. Wahana yang bagus bagi setiap capres untuk memperkenalkan diri kepada
masyarakat, memaparkan visi, program, pengalaman, serta unjuk kebolehan dalam
berkomunikasi. Tapi, lebih dari sekadar show, debat capres dimaksudkan untuk memberikan
referensi kepada masyarakat tentang calon pemimpinnya. Karena itu, debat capres harus
benar-benar menjadi rujukan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politik.
Jika benar debat capres menjadi rujukan, apa yang dirujuk? Substansi persoalan atau
penampilan diri capres? Kualitas program atau kemampuan berkomunikasi capres? Untuk
menjawab pertanyaan ini, setidak-tidaknya ada dua persoalan yang perlu diungkapkan.
Pertama, debat capres semestinya adalah panggung tempat masyarakat dapat
mengidentifikasi distingsi diri calon pemimpin. Kenyataannya, dalam debat capres di
Indonesia sejauh ini, para capres ibaratnya "serupa tapi tak sama". Mereka ramai-ramai
menghampiri khalayak dengan slogan dan janji tentang pengentasan masyarakat dari
kemiskinan, pengangguran, percepatan pembangunan, pemberantasan korupsi, dan
seterusnya. Tidak ada capres yang tidak mengangkat masalah tersebut dengan sudut pandang
yang tak jauh berbeda.
Debat capres 2014 juga belum sepenuhnya beranjak dari paradoks tersebut: maunya menjadi
ajang unjuk eksistensi diri yang distingtif, tapi justru menjadi ajang unjuk kemiripan. Sulit
untuk menemukan hal yang benar-benar baru dari capres-cawapres. Program, janji, dan skala
prioritas yang mereka sampaikan sudah disampaikan berbagai pihak dalam beragam forum
publik.
Kedua, para capres membahas dan menjanjikan terlalu banyak hal. Bisa jadi hal ini karena
memang masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia juga sangat beragam dan
semuanya membutuhkan perhatian seorang presiden. Tapi menyampaikan dan menjanjikan
terlalu banyak hal dalam satu kesempatan dapat menyulitkan khalayak untuk
mengidentifikasi apa sesungguhnya prioritas seorang capres dibanding capres lain. Tantangan
seorang capres dalam hal ini adalah menegaskan distingsi diri.
Masyarakat berpendidikan tinggi barangkali tidak kesulitan menilai kualitas capres dari
beberapa kali debat capres. Tapi, bagaimana dengan masyarakat Indonesia pada umumnya?
Jika persoalan ini tidak dipecahkan, bisa-bisa debat capres tidak mempunyai pengaruh
signifikan terhadap pilihan politik masyarakat. Pilihan politik masyarakat ditentukan banyak
faktor. Bentuk-bentuk kampanye, termasuk debat capres, hanya salah satu faktor. Apalagi
jika debat capres itu belum menemukan bentuk yang benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Kemungkinan lain, debat capres mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap pilihan
politik masyarakat. Tapi masyarakat umumnya hanya berfokus pada penampilan diri capres.
Karena pemaparan gagasan dan diskusi yang terjadi menurut ukuran orang awam terlalu di
awang-awang atau telanjur banal karena sudah sering diutarakan para politikus saat pemilu,
masyarakat kemudian notabene hanya memperhatikan apakah seorang capres cukup gagah,
tampak berwibawa, jago berpidato, menguasai panggung, dan seterusnya. Penampilan diri
seorang capres memang penting, tapi penampilan diri semata dapat menipu dan menyesatkan.
*
Agenda Penyiaran untuk Presiden Baru
Sabtu, 28 Juni 2014
Roy Thaniago, Direktur Remotivi
Isu penyiaran masih menjadi sebuah perbincangan yang sepi. Padahal penyiaran berperan
vital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di abad ini TV telah menjadi salah satu
aktor utama dalam memilih-mengatur agenda publik, membingkai sebuah peristiwa dan nilai,
hingga membentuk persepsi masyarakat. Pun, ia merupakan mesin ekonomi dan politik yang
dominan.
Karena itu, negara harus mengawasi penggunaannya secara benar dan adil. Ironisnya,
pemerintahan SBY gagal menjadikan penyiaran sebagai sektor yang bisa memberikan
keuntungan yang adil bagi seluruh warga negara. Sebab, yang menikmati keuntungan barulah
para konglomerat media dan elite politik. Tidak bagi buruh media, apalagi publik luas.
Maka saya terkesan oleh salah satu poin visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla: "Kami akan
menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup
orang banyak, sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang
(kartel) industri penyiaran".
Sesungguhnya, tak ada gagasan baru dalam poin tersebut. Yang baru adalah ikhtiar dan
perhatian atasnya. Di tengah sikap negara yang abai terhadap penyiaran, meletakkannya
dalam agenda kerja politik adalah suatu yang berharga bagi publik.
Saya mencatat ada empat agenda utama yang perlu diperhatikan, yakni (1) konglomerasi
media, (2) sentralisasi penyiaran di Jakarta, (3) penguatan Komisi Penyiaran Indonesia, dan
(4) penguatan lembaga penyiaran komunitas.
Praktek konglomerasi di banyak negara menunjukkan bahwa dominasi seseorang atau suatu
kelompok atas kepemilikan media berbahaya bagi demokrasi. Dalam demokrasi,
konglomerasi adalah ide yang ditolak. Sebab, konglomerasi merupakan sebentuk kekerasan
simbolik terhadap apa yang dicita-citakan dalam ruang publik: kesetaraan dan keadilan.
Konglomerasi merampas peluang tiap orang untuk bisa berdiri sejajar.
Nyatanya, dari ribuan media di Indonesia, kepemilikannya hanya ada di tangan 12 kelompok
bisnis (Lim, 2011; Nugroho, 2012). Seseorang secara sekaligus bisa memiliki puluhan stasiun
TV, media cetak, radio, dan online. Menyedihkannya, praktek monopoli ini dibiarkan, malah
"difasilitasi" melalui berbagai peraturan turunan undang-undang.
Lalu masalah sentralisasi-di mana 10 stasiun TV Jakarta bisa menjangkau publik nasional-
yang sesungguhnya mengancam keragaman di Indonesia. Secara hiperbolis bisa dikatakan
bahwa stasiun TV Jakarta menentukan dan mengatur apa dan bagaimana 240 juta orang
Indonesia bercakap-cakap. Situasi ini jelas merugikan publik secara ekonomi, politik, dan
budaya (Armando, 2011). Akibatnya, bisnis stasiun TV lokal menjadi tak sehat, diskursus
politik lokal tak mendapat panggung, dan Indonesia tengah di-Jakarta-nisasi. Sebenarnya UU
Penyiaran telah melarang stasiun TV bersiaran nasional dan mewajibkannya menjalankan
Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Tapi penegakannya mati suri, dan pemerintah seolah lebih
melayani keinginan industri.
Dua agenda lain adalah sesuatu yang sifatnya pemberdayaan publik. Publik mesti didorong
menjadi aktor, bukan penonton. Wacana penguatan publik harus dimulai dengan menguatkan
lembaga perwakilan publik, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kewenangan lembaga
ini harus ditambah, sehingga perannya bisa lebih optimal. Ambiguitas peran yang berbagi
dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mesti diperjelas dengan perlahan
memindahkan beberapa otoritas pemerintah ke KPI. Pendek kata, kita harus bermimpi punya
KPI yang sekuat KPK.
Menguatkan KPI juga mesti berbarengan dengan memberikan peluang bagi publik untuk
terlibat dalam memanfaatkan sektor penyiaran. Pada konteks inilah agenda penguatan
lembaga penyiaran komunitas (LPK) mendapatkan tempat. LPK bisa menjadi cara publik
berdaulat dan menyediakan informasi alternatif yang baik dan relevan dengan kebutuhannya.
Dan ini sesuai dengan visi Jokowi-Kalla: membangun Indonesia dari pinggiran.
Pekerjaan mereformasi sektor penyiaran adalah pekerjaan yang berat. Upaya mengaturnya
akan berbalas serangan balik dari media itu sendiri. Argumen "kebebasan pers" akan
digunakan untuk menjustifikasi keliaran libido ekonomi para konglomerat media. Maka
presiden baru nantinya ditantang untuk berani tidak populer di media karena telah melakukan
yang benar.
Jokowi, yang selama ini dekat dengan media, ditantang untuk tunduk terhadap konstitusi,
bukan konstituen. Apalagi, dalam koalisi politik yang mengusungnya sebagai capres terdapat
Partai NasDem, yang mana pimpinannya, Surya Paloh, adalah pengusaha media yang terbukti
telah menggunakan Metro TV untuk kepentingan politik kelompoknya. Nah, apakah Jokowi
punya nyali dalam mengoreksi praktek keliru yang dilakukan para pendukungnya tersebut?
Sebelum nyali, mungkin Jokowi harus memulainya dari soal pemahaman mengenai
frekuensi. Frekuensi, yang dipakai oleh stasiun TV dan radio untuk bersiaran itu, adalah milik
publik. Jadi, apa pun peruntukannya harus bermanfaat bagi publik. Ia tidak bisa dipakai untuk
"serangan udara" demi memenangkan pilpres. *
Anda mungkin juga menyukai
- Pendapat 2016Dokumen339 halamanPendapat 2016ekho109Belum ada peringkat
- Puisi-Puisi Goenawan Mohamad Di Kompas 20 September 2015Dokumen6 halamanPuisi-Puisi Goenawan Mohamad Di Kompas 20 September 2015ekho109Belum ada peringkat
- Pendapat 2017Dokumen155 halamanPendapat 2017ekho109Belum ada peringkat
- Resonansi Azyumardi Azra 2015Dokumen136 halamanResonansi Azyumardi Azra 2015ekho109Belum ada peringkat
- Imam Al-Ghazali - Kitab Kimyatusy Sya'Adah (Kimia Kebahagiaan)Dokumen66 halamanImam Al-Ghazali - Kitab Kimyatusy Sya'Adah (Kimia Kebahagiaan)ekho109100% (1)
- Quraish Shihab - Membumikan Al QuranDokumen219 halamanQuraish Shihab - Membumikan Al Quranekho109100% (5)
- (Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 28 Maret 2016-9 Mei 2016Dokumen189 halaman(Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 28 Maret 2016-9 Mei 2016ekho109Belum ada peringkat
- (Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 25 Juli 2015-5 September 2015Dokumen163 halaman(Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 25 Juli 2015-5 September 2015ekho109Belum ada peringkat
- Resonansi Asma Nadia 2015Dokumen151 halamanResonansi Asma Nadia 2015ekho109Belum ada peringkat
- Daoed Joesoef - EmakDokumen231 halamanDaoed Joesoef - Emakekho109100% (2)
- Al-Ghazali - Kitab Bidayatul HidayahDokumen52 halamanAl-Ghazali - Kitab Bidayatul Hidayahekho109100% (2)
- Nahdlatul Ulama Dan Pancasila (Oleh Einar M. Sitompul)Dokumen259 halamanNahdlatul Ulama Dan Pancasila (Oleh Einar M. Sitompul)ekho109Belum ada peringkat
- (Sindonews - Com) Opini Sosial-Budaya 21 Juli 2015-3 September 2015Dokumen162 halaman(Sindonews - Com) Opini Sosial-Budaya 21 Juli 2015-3 September 2015ekho109Belum ada peringkat
- (Sindonews - Com) Opini Ekonomi Koran Sindo 15 Juni 2015-1 September 2015Dokumen156 halaman(Sindonews - Com) Opini Ekonomi Koran Sindo 15 Juni 2015-1 September 2015ekho109Belum ada peringkat
- Artikel Pilihan Media Indonesia Minggu 3 Mei 2015Dokumen55 halamanArtikel Pilihan Media Indonesia Minggu 3 Mei 2015ekho109Belum ada peringkat
- (Sindonews - Com) Opini Sosial-Budaya 6 Juni 2015-20 Juli 2015Dokumen155 halaman(Sindonews - Com) Opini Sosial-Budaya 6 Juni 2015-20 Juli 2015ekho109Belum ada peringkat
- (Sindonews - Com) Opini Ekonomi Koran Sindo 27 November 2014-11 Februari 2015Dokumen154 halaman(Sindonews - Com) Opini Ekonomi Koran Sindo 27 November 2014-11 Februari 2015ekho109Belum ada peringkat
- (Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 22 Mei 2015-24 Juli 2015Dokumen153 halaman(Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 22 Mei 2015-24 Juli 2015ekho109Belum ada peringkat
- Artikel Pilihan Media Indonesia Minggu 4 Januari 2015Dokumen44 halamanArtikel Pilihan Media Indonesia Minggu 4 Januari 2015ekho109Belum ada peringkat
- (Sindonews - Com) Opini Sosial Budaya Koran SINDO 22 Desember 2014-23 Januari 2015Dokumen186 halaman(Sindonews - Com) Opini Sosial Budaya Koran SINDO 22 Desember 2014-23 Januari 2015ekho109Belum ada peringkat
- The Voice of God: Experience A Life Changing Relationship with the LordDari EverandThe Voice of God: Experience A Life Changing Relationship with the LordBelum ada peringkat
- From Raindrops to an Ocean: An Indian-American Oncologist Discovers Faith's Power From A PatientDari EverandFrom Raindrops to an Ocean: An Indian-American Oncologist Discovers Faith's Power From A PatientPenilaian: 1 dari 5 bintang1/5 (1)