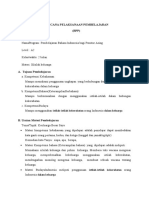Chapter II PDF
Chapter II PDF
Diunggah oleh
Azira NatasyaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Chapter II PDF
Chapter II PDF
Diunggah oleh
Azira NatasyaHak Cipta:
Format Tersedia
BAB II
KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep
2.1.1 Afiks dan Afiksasi
Ramlan (1983 : 48) menyatakan bahwa afiks ialah suatu satuan gramatik
terikat yang di dalam suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok
kata, yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk
kata atau pokok kata baru. Misalnya kata minuman. Kata ini terdiri dari dua unsur,
ialah minum yang merupakan kata dan –an yang merupakan satuan terikat. Maka
morfem –an diduga merupakan afiks. Setiap afiks berupa satuan terikat, artinya
dalam tuturan biasa tidak dapat berdiri sendiri, dan secara garamatikal selalu melekat
pada satuan lain. Afiks-afiks yang terletak di lajur paling depan disebut prefiks
karena selalu melekat di depan bentuk dasar; yang terletak di jalur tengah disebut
infiks karena selalu melekat di tengah bentuk dasar, dan yang terletak di lajur
belakang disebut sufiks karena selalu melekat di belakang bentuk dasar. Ketiga
macam afiks itu biasa juga disebut awalan, sisipan, dan akhiran (Ramlan, 1983 : 50).
Menurut Cahyono (1995 : 141) morfem terikat itu ialah afiks. Morfem ini
tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki arti sebelum melekat pada satuan lain.
Berdasarkan kedudukan morfem terikat dengan morfem bebas itu, pembubuhan
dapat dibedakan menjadi empat, yaitu pembubuhan depan, pembubuhan tengah,
pembubuhan akhir, dan pembubuhan terbelah (Parera, 1988 dalam Cahyono, 1995 :
145). Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Fromkin dan Rodman (1998:519
Universitas Sumatera Utara
dalam Yogianto, 2010) yang menyatakan bahwa afiks adalah morfem terikat yang
dilekatkan pada morfem dasar atau akar.
Sementara itu, Muslich (2008 : 41) mengemukakan bahwa afiks ialah bentuk
kebahasaan terikat yang hanya mempunyai arti gramatikal, yang merupakan unsur
langsung suatu kata, tetapi bukan merupakan bentuk dasar, yang memiliki
kesanggupan untuk membentuk kata-kata baru.
Afiksasi (affixation) adalah penambahan dengan afiks (affix). Afiks itu selalu
berupa morfem terikat, dan dapat ditambahkan pada awal kata (prefiks; prefix) dalam
proses yang disebut prefiksasi (prefixation), pada akhir kata (sufiks; suffix) dalam
proses yang disebut sufiksasi (suffixation), untuk sebagian pada awal kata serta untuk
sebagian pada akhir kata (konfiks, ambifiks, atau simulfiks; confix, ambifix, simulfix)
dalam proses yang disebut konfiksasi, ambifiksasi atau simulfiksasi (confixation,
ambifixation, simulfixation), atau di dalam kata itu sendiri sebagai suatu “sisipan”
(infiks; infix) dalam proses yang disebut infiksasi (infixation) (Verhaar, 1988 : 60).
Samsuri (1994 : 190) menyatakan bahwa afiksasi yaitu penggabungan akar
atau pokok dengan afiks (-afik).
Kridalaksana berpendapat bahwa afiksasi adalah proses yang mengubah
leksem menjadi kata kompleks. Dalam proses ini, leksem (1) berubah bentuknya, (2)
menjadi kategori tertentu, sehingga berstatus kata (atau bila telah berstatus kata
berganti kategori), (3) sedikit banyak berubah maknanya (1996 : 28). Selanjutnya ia
menambahkan bahwa proses afiksasi bukanlah hanya sekadar perubahan bentuk saja,
melainkan juga pembentukan leksem menjadi kelas kata tertentu (1996 : 32). Jenis
afiks secara tradisional dapat diklasifikasikan atas:
a. Prefiks, yaitu afiks yang diletakkan di muka dasar,
Universitas Sumatera Utara
Contoh: me-, di-, ber-, ke-, ter-, pe-, per-, se-,
b. Infiks, yaitu afiks yang diletakkan di dalam dasar,
Contoh: -el-, -er-, -em-, dan –in-.
c. Sufiks, yaitu afiks yang diletakkan di belakang dasar,
Contoh: -an, -kan, -i.
d. Simulfiks, yaitu afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental
yang dileburkan pada dasar. Dalam bahasa Indonesia simulfiks
dimanifestasikan dengan nasalisasi dari fonem pertama suatu bentuk
dasar, dan fungsinya ialah membentuk verba atau memverbalkan nomina,
ajektiva atau kelas kata lain. Contoh berikut terdapat dalam bahasa
Indonesia non-standar: kopi-ngopi, soto-nyoto, sate-nyate, kebut-ngebut.
e. Konfiks, yaitu afiks yang terdiri dari dua unsur, satu di muka bentuk dasar
dan satu di belakang bentuk dasar; dan berfungsi sebagai salah satu
morfem terbagi.
Contoh: ke-an, pe-an, per-an, dan ber-an (Kridalaksana, 1996 : 29).
Proses afiksasi dimungkinkan oleh dua hal pokok yaitu adanya afiks
(imbuhan) dan bentuk dasar. Proses pembubuhan afiks (afiksasi) ialah peristiwa
pembentukan kata dengan jalan membubuhkan afiks pada bentuk dasar (Muslich,
2008 : 38). Menurutnya, segala morfem imbuhan, baik imbuhan awal (prefiks),
imbuhan tengah (infiks), imbuhan akhir (sufiks), maupun imbuhan terbelah (konfiks
atau simulfiks), dapat bergabung dengan bentuk dasar bebas.
Universitas Sumatera Utara
2.1.2 Bahasa Nias
Bahasa Nias merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh sekelompok
masyarakat yang terdapat di Sumatera Utara, tepatnya di sebelah barat pulau
Sumatera yang dikenal dengan nama Pulau Nias. Dalam wikipedia (2010) dikatakan
bahwa Pulau Nias disebut dengan istilah Tanö Niha yang berasal dari kata Tanö
(tanah) dan Niha (manusia).
Penduduk asli pulau Nias dikenal dengan sebutan suku Nias. Suku Nias
adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih
tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut fondrakö, yang mengatur segala segi
kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian.
Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik (suatu istilah yang
menunjuk pada peninggalan-peninggalan budaya prasejarah yang menggunakan
batu-batu besar). Hal ini dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada
batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai
sekarang.
Penduduk Nias masih mengandalkan hasil pertanian sebagai penghasilan
utamanya hingga saat ini. Hal tersebut didukung oleh alam Nias yang menawarkan
lahan potensial untuk dibudidayakan. Hasil-hasil pertanian yang terdapat di Nias
antara lain yaitu karet, kelapa, kopi, cengkeh dan nilam.
Hampir seluruh masyarakat Nias menggunakan bahasa Nias sebagai alat
komunikasi. Bahasa yang dikenal dengan ciri khasnya yang tidak memiliki konsonan
di akhir fonem ini juga merupakan bahasa pertama bagi anak-anak. Namun, dengan
diberlakukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan,
maka bahasa Indonesia memiliki peluang untuk digunakan sebagai media
Universitas Sumatera Utara
komunikasi dalam berinteraksi. Hal ini juga ikut dipengaruhi oleh mobilitas
penduduk yang semakin dinamis dan perkembangan teknologi yang sekarang bisa
menjalar ke pelosok-pelosok.
Gambaran tentang pulau Nias dapat dilihat pada peta berikut:
PETA PULAU NIAS
Universitas Sumatera Utara
2.2 Landasan Teori
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori morfologi struktural.
Morfologi struktural merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji struktur
dan proses pembentukan kata. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta
pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, atau
dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk
kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun
fungsi semantik (Ramlan, 1983 : 16). Ilmu morfologi menyangkut struktur “internal”
(Verhaar, 2001 : 11). Verhaar (2001) juga berpendapat bahwa cabang yang namanya
“morfologi” mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan
gramatikal. Morfologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji bentuk bahasa
serta pengaruh perubahan bentuk bahasa pada fungsi dan arti kata. Sasaran
pengkajian dalam morfologi ialah kata dan morfem (Cahyono, 1995 : 140).
Dalam membentuk sebuah kata dikenal adanya proses morfologis. Menurut
Samsuri (1994 : 190), cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem
yang satu dengan morfem yang lain disebut proses morfologis. Pembentukan kata-
kata ini melalui beberapa proses yaitu proses pembubuhan afiks (afiksasi), proses
pengulangan (reduplikasi), dan proses pemajemukan. Proses pembubuhan afiks ialah
pembubuhan afiks pada sesuatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal
maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata. Proses pengulangan ialah
pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan
variasi fonem maupun tidak. Proses pemajemukan ialah penggabungan dua kata yang
menimbulkan suatu kata baru (Ramlan, 1983 : 47, 55, 67).
Universitas Sumatera Utara
Proses morfologis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah proses
pembubuhan afiks. Hal ini sejalan dengan topik yang diteliti oleh peneliti, yaitu
proses afiksasi dalam bahasa Nias.
Pengertian afiksasi atau pengimbuhan menurut Putrayasa (2008 : 5) adalah
proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks (imbuhan) pada bentuk dasar,
baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks.
Menurut Verhaar (2001 : 107-108) afiks ada 4 macam:
a. Prefiks, yang diimbuhkan di sebelah kiri dasar dalam proses yang disebut
“prefiksasi”.
Contoh: prefiks {men-} seperti dalam: mencuri, menyalak, melintang, dan
merintis; prefiks {pen-} seperti dalam pengurus, pemarah, pencipta, dan
penyatu; prefiks {ke-} dalam kedua, ketiga; prefiks {se-} seperti dalam
setinggi dan sesuai; {ber-} seperti dalam berjuang, belajar; {memper-}
seperti dalam memperbanyak atau memperkuat.
b. Sufiks, yang diimbuhkan di sebelah kanan dasar dalam proses yang
disebut “ sufiksasi”.
Contoh: sufiks {-an}, seperti dalam akhiran dan tuntutan, {-wan} dan {-
wati} seperti dalam wartawan dan wartawati; {-ku}, {-mu} dan {-nya}
seperti dalam permainanku, permainanmu dan permainannya.
c. Infiks, yang diimbuhkan dengan penyisipan di dalam dasar itu, dalam
proses yang namanya “infiksasi”.
Contoh: infiks {-in-} dalam kata kesinambungan.
d. Konfiks, atau simulfiks, atau ambifiks, atau sirkumfiks, yang diimbuhkan
untuk sebagian di sebelah kiri dasar dan untuk sebagian di sebelah
Universitas Sumatera Utara
kanannya, dalam proses yang dinamai “konfiksasi, atau “simulfiksasi”,
atau “ambifiksasi”, atau “sirkumfiksasi”.
Contoh: konfiks {men-kan}, {memper-kan}, {men-i}, {memper-i} seperti
dalam menyembelihkan, mempermainkan, menduduki, dan memperingati;
{ke-an}seperti dalam keindahan, ketinggian.
Proses pembubuhan afiks pada morfem lain sering diikuti dengan perubahan-
perubahan fonem. Perubahan itu bisa berupa perubahan fonem ke fonem lain,
penambahan fonem, dan penghilangan fonem. Contoh: morfem afiks {meN-} yang
memiliki tiga fonem, yaitu /m/, /e/, dan /N/, setelah bergabung dengan bentuk dasar
potong, fonem /N/ berubah menjadi /m/, sehingga pertemuan itu menghasilkan kata
memotong. Dengan demikian, pada proses morfologis itu terjadi pula proses
morfofonemis yang berupa perubahan fonem, yaitu perubahan fonem /N/ menjadi
/m/: {meN] {mem} (Muslich, 2008 : 41).
Proses pembubuhan afiks meliputi fungsi dan arti. Fungsi ialah kemampuan
morfem untuk membentuk kelas kata tertentu (Muslich, 2008 : 94). Dalam hal ini,
yang dimaksud dengan morfem yang membentuk kelas kata itu adalah morfem
imbuhan.
Contoh 1:
Bentuk dasar gergaji yang berkelas kata benda apabila mendapatkan morfem
imbuhan {meN-} akan menjadi kelas kata kerja (menggergaji). Dari contoh ini
dapat diketahui bahwa prefiks {meN-} berfungsi untuk membentuk kata kerja.
Universitas Sumatera Utara
Contoh 2:
Bentuk dasar malas yang berkelas kata sifat apabila mendapatkan morfem
imbuhan {peN-} akan menjadi kelas kata benda (pemalas). Dari contoh ini dapat
diketahui bahwa prefiks {peN-} berfungsi untuk membentuk kata benda.
Contoh 3:
Bentuk dasar makan yang berkelas kata kerja apabila mendapatkan morfem
imbuhan {-an} akan menjadi kelas kata benda (makanan). Dari contoh ini dapat
diketahui bahwa sufiks {-an} berfungsi untuk membentuk kata benda.
Contoh 4:
Bentuk dasar wibawa yang berkelas kata benda apabila mendapatkan morfem
imbuhan {ber-} akan menjadi kelas kata sifat (berwibawa). Dari contoh ini dapat
diketahui bahwa prefiks {ber-} berfungsi untuk membentuk kata sifat.
Contoh 5:
Bentuk dasar lelah yang berkelas kata sifat apabila mendapatkan morfem
imbuhan {ke-an} akan menjadi kelas kata kerja (kelelahan). Dari contoh ini dapat
diketahui bahwa konfiks {ke-an} berfungsi untuk membentuk kata kerja.
Contoh 6:
Bentuk dasar ikat yang berkelas kata kerja apabila mendapatkan morfem
imbuhan {ter-} akan menjadi kelas kata sifat (terikat). Dari contoh ini dapat
diketahui bahwa prefiks {ter-} berfungsi untuk membentuk kata sifat.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembubuhan afiks pada kata
dapat menyebabkan perubahan golongan kata. Perubahan golongan kata ini dapat
berupa perubahan dari golongan kata benda menjadi kata kerja ataupun sebaliknya,
dari golongan kata sifat menjadi kata benda ataupun sebaliknya, dan dari golongan
Universitas Sumatera Utara
kata sifat menjadi kata kerja atau dari golongan kata kerja menjadi kata sifat.
Perubahan-perubahan tersebut tentu saja tidak terlepas dari imbuhan yang melekati
bentuk dasar dari golongan kata tertentu.
Arti atau nosi adalah arti yang ditimbulkan oleh proses afiksasi. Arti ini
timbul sebagai akibat bergabungnya morfem satu dengan yang lain. Muslich (2008 :
66) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan arti pada pembicaraan ini bukanlah
arti suatu kata yang terdapat dalam kamus, arti leksikal, tetapi arti sebagai akibat
bergabungnya morfem satu dengan yang lain, arti struktural atau arti gramatikal.
Jika fungsi gramatik disebut sebagai fungsi, maka fungsi semantik disebut
sebagai arti atau nosi dalam proses pengimbuhan morfem. Arti morfem imbuhan
selalu bergantung pada kelas kata bentuk dasarnya. Selain itu, arti morfem imbuhan
tidak dapat dipisahkan dengan fungsi morfem itu sendiri.
Contoh 1:
Prefiks{meN-} mempunyai arti ‘melakukan tindakan seperti yang tersebut
pada bentuk dasarnya’. Misalnya, dalam kata membaca, menendang, mengantar.
Contoh 2:
Infiks {-er-} mempunyai arti ‘menyatakan banyak dan bermacam-macam’.
Misalnya dalam kata gigi-gerigi, sabut-serabut, titik-teritik.
Contoh 3:
Sufiks {-i} mempunyai arti ‘menyatakan intensitas, pekerjaan yang
dilangsungkan berulang-ulang (frekuentatif), atau pelakunya lebih dari satu orang.
Misalnya, dalam kata menembaki, melontari, melompati.
Universitas Sumatera Utara
Contoh 4:
Konfiks {me-kan} mempunyai arti ‘menjadikan sesuatu atau menganggap
sebagai ‘. Misalnya, dalam kata-kata memperhambakan, mempermasalahkan.
2.3 Tinjauan Pustaka
Penelitian terhadap proses pembentukan kata, khususnya terhadap proses
afiksasi pernah dilakukan sebelumnya. Tambun (1980) dalam skripsinya yang
berjudul “Perbandingan Afiksasi antara Bahasa Alas dengan Bahasa Indonesia”
membandingkan afiksasi bahasa Alas dengan afiksasi bahasa Indonesia yang
meliputi prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Menurutnya, terdapat perbedaan dan
persamaan antara afiksasi bahasa Alas dengan bahasa Indonesia.
Syafii (1981), dalam skripsinya yang berjudul “Afiksasi Bahasa Kurinci
Tanjung Morawa” melakukan penelitian terhadap afiksasi dalam bahasa Kurinci.
Namun, penelitiannya dibatasi pada afiks yang produktif saja, seperti prefiks, sufiks,
dan konfiks.
Kasmi (1981), dalam skripsinya yang berjudul “Pemakaian Prefiks dalam
Bahasa Minangkabau” mengkaji tentang pembagian prefiks dalam bahasa
Minangkabau yang melingkupi bentuk, distribusi, fungsi dan nosi dari prefiks
tersebut.
Selain itu, dalam skripsi yang berjudul “Morfologi Bahasa Jawa Dialek
Gebang” (1981), Deliana meneliti morfologi dalam bahasa Jawa dialek Gebang yang
meliputi afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan klitisasi.
Penelitian tentang morfologi juga pernah dilakukan oleh Amilah (1982)
dalam skripsinya yang berjudul “Morfologi Bahasa Melayu Dialek Asahan”. Ia
Universitas Sumatera Utara
meneliti tentang morfologi dan proses morfologis yang di dalamnya mencakup
tentang awalan (prefiks) dan akhiran (sufiks).
Purba (1984), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Komparatif antara
Prefiks Bahasa Nias dengan Prefiks Bahasa Pakpak Dairi” membahas persamaan
dan perbedaan prefiks antara kedua bahasa tersebut. Penelitian ini kemudian
dilanjutkan oleh Siahaan (1986) dalam skripsi yang judulnya sama, tetapi dengan
penguraian yang agak berbeda dari peneliti sebelumnya. Menurut Purba prefiksasi
adalah proses pembubuhan afiks atau imbuhan di depan kata dasar/pelekatan kepada
kata dasar dan membentuk kesatuan arti, sedangkan menurut Siahaan prefiksasi ialah
proses penambahan prefiks di awal bentuk dasar. Dari kedua skripsi tersebut
dijelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara prefiks bahasa Nias
dengan prefiks bahasa Pakpak Dairi. Prefiks dalam bahasa Nias terdiri atas /maN-/,
/mo-/, /me-/, /mu-/, /la-/, /i-/, /te-/, /faN-/, /fa-/, /aN-/, /a-/, /da-/, /saN-/, sedangkan
prefiks dalam bahasa Pakpak Dairi terdiri atas /meN-/, /i-/, /ter-/, /pe-/, /per-/, /me-/,
/se-/, /ki-/, /N-/.
Bangun (1985) membandingkan prefiks bahasa Nias dengan bahasa Dairi
dalam skripsinya yang berjudul “Suatu Tinjauan Komparatif Perbandingan Prefiks
Bahasa Nias dengan Bahasa Dairi”. Menurutnya prefiks dalam bahasa Nias terdiri
atas /mo-/, /fa-/, /me-/, /faN-/, /maN-/, /i-/, /te-/, /mu-/, /saN-/, /da-/, /la-/, /a-/, /aN-/,
sedangkan prefiks bahasa Pakpak Dairi terdiri atas /men-/, /ter-/, /me-/, /pe-/, /per-/,
/i-/, /ki-/, /se-/, /N-/. Prefiks dari kedua bahasa tersebut memiliki persamaan dan
perbedaan. Berdasarkan pengamatan peneliti, skripsi Bangun tidak menjelaskan
proses morfofonemik yang terjadi dalam prefiksasi kedua bahasa yang ditelitinya.
Selain itu, pemakaian lambang morfem dalam skripsi tersebut kurang tepat karena
Universitas Sumatera Utara
lambang yang digunakannya adalah lambang fonetis. Hal lain yang juga tidak luput
dari pengamatan peneliti adalah setiap kata ‘prefiks’ dalam skripsi tersebut selalu
dituliskan dengan kata ‘prepiks’.
Butet Popy (1987), dalam skripsinya yang berjudul “Afiksasi Bahasa Pesisir
Sibolga” membahas tentang afiksasi yang terdapat dalam bahasa Pesisir Sibolga.
Menurutnya afiks atau imbuhan ialah bentuk linguistik yang dapat melekat pada
berbagai-bagai kata untuk membentuk kata baru. Ia membahas tentang prefiks,
sufiks, dan simulfiks dalam bahasa Pesisir Sibolga.
Sembiring (1992), dalam skripsinya yang berjudul “Perbandingan Afiksasi
antara Bahasa Batak Karo dengan Bahasa Nias” membahas perbedaan dan
persamaan afiksasi antara kedua bahasa tersebut. Penelitiannya dibatasi pada prefiks,
infiks, dan sufiks. Sembiring menjelaskan bahwa afiksasi adalah pembubuhan afiks
pada bentuk dasar, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan baik dalam jenis
bentuk dan arti. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa prefiks dalam bahasa Nias terdiri
atas /man-/, /me-/, /mo-/, /mu-/, /la-/, /i-/, /te-/, /fan-/, /fa-/, /an-/, /da-/, /san-/, /a-/;
infiks hanya satu, yaitu /-ga-/; sufiks terdiri atas /-o/, /-go/, /-fo/, /-ni/, /-si/, /-ma/, /-i/,
/-so/, /-ta/, /-wa/, /-to/, /-nia/, /-la/, /-sa/, /-a/. Menurutnya terdapat persamaan dan
perbedaan antara bahasa Batak Karo dan bahasa Nias.
Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Sembiring adalah dalam
skripsi ini dijelaskan proses afiksasi yang meliputi prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks
sedangkan penelitian Sembiring dibatasi pada prefiks, infiks dan sufiks saja. Dalam
skripsi Sembiring dibandingkan dua bahasa sedangkan pada penelitian ini tidak ada
perbandingan dua bahasa. Selain itu, dalam skripsi ini diuraikan proses
morfofonemik tiap-tiap afiks, sedangkan dalam skripsi Sembiring tidak diuraikan.
Universitas Sumatera Utara
Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Morfologis pada Novel La Barka
Karya Nh. Dini (1994), Harsani mengkaji proses morfologis pada novel tersebut
yang meliputi afiksasi, pengulangan, dan pemajemukan.
Nilawijaya (1997) membahas tentang morfem bebas dan morfem terikat,
proses morfologis (afiksasi, reduplikasi, dan kompositum) bahasa Melayu
Palembang dalam skripsinya yang berjudul “Morfologi Bahasa Melayu Palembang”.
Siregar (2000), dalam skripsinya yang berjudul “Morfologi Kata Kerja
Bahasa Angkola” membahas tentang morfologi kata kerja bahasa Angkola yang
meliputi ciri morfologis, sintaksis, semantis, dan bentuk kata kerja. Ia juga
membahas tentang reduplikasi dan kata kerja berimbuhan.
Perbandingan prefiks antara dua bahasa dilakukan oleh Siagian (2009) dalam
skripsinya yang berjudul “Perbandingan Prefiks Bahasa Indonesia dengan Prefiks
Bahasa Batak Toba”. Ia membandingkan antara prefiks bahasa Indonesia dan prefiks
bahasa Batak Toba dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan prefiks dari kedua
bahasa tersebut.
Dari penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa pembentukan kata,
khususnya afiksasi, mencakup jenis-jenis afiks itu sendiri serta hal-hal yang meliputi
proses pengimbuhannya, seperti bentuk afiks, distribusi afiks, juga fungsi dan makna
afiks tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi informasi dan acuan bagi
peneliti saat ini dalam meneliti afiksasi bahasa Nias.
Dalam penelitian ini, peneliti sendiri mengkaji tentang afiksasi dalam bahasa
Nias dialek Gunungsitoli yang meliputi prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Proses
pembubuhan afiks dalam bahasa Nias ini mencakup bentuk, distribusi, fungsi, dan
nosi.
Universitas Sumatera Utara
Anda mungkin juga menyukai
- CJR Manajemen Sekolah Azira NatasyaDokumen19 halamanCJR Manajemen Sekolah Azira NatasyaAzira NatasyaBelum ada peringkat
- PragmatoklllllllDokumen10 halamanPragmatoklllllllAzira NatasyaBelum ada peringkat
- Putri Alit Pamungkas - 1401036024Dokumen153 halamanPutri Alit Pamungkas - 1401036024Azira NatasyaBelum ada peringkat
- PuisiDokumen1 halamanPuisiAzira NatasyaBelum ada peringkat
- Sudah-AbstrakDokumen1 halamanSudah-AbstrakAzira NatasyaBelum ada peringkat
- CBR Pengembangan Bahan Ajar ZiraDokumen15 halamanCBR Pengembangan Bahan Ajar ZiraAzira NatasyaBelum ada peringkat
- Khadijah - Kisah Shahabiyah.Dokumen8 halamanKhadijah - Kisah Shahabiyah.Azira NatasyaBelum ada peringkat
- RPP Bipa 1-3Dokumen9 halamanRPP Bipa 1-3Azira NatasyaBelum ada peringkat
- Teks Makro Dan Mikro Kelompok 8Dokumen8 halamanTeks Makro Dan Mikro Kelompok 8Azira NatasyaBelum ada peringkat
- Essay Manajemen PendidikanDokumen4 halamanEssay Manajemen PendidikanAzira Natasya100% (1)
- Outline Dina Sri NitamiDokumen6 halamanOutline Dina Sri NitamiAzira NatasyaBelum ada peringkat
- Cover MR SemantikDokumen1 halamanCover MR SemantikAzira NatasyaBelum ada peringkat
- 54Dokumen3 halaman54Azira NatasyaBelum ada peringkat
- 54Dokumen3 halaman54Azira NatasyaBelum ada peringkat
- Artikel Dongeng Melatih Imajinasi AnakDokumen3 halamanArtikel Dongeng Melatih Imajinasi AnakAzira NatasyaBelum ada peringkat
- CBR BindoDokumen16 halamanCBR BindoAzira NatasyaBelum ada peringkat
- Filsafat MandiriDokumen16 halamanFilsafat MandiriAzira NatasyaBelum ada peringkat