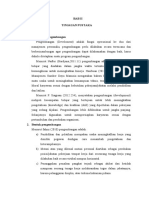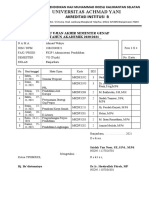Identifikasi Perkembangan Wilayah Kab - Banjar
Identifikasi Perkembangan Wilayah Kab - Banjar
Diunggah oleh
Iky FransiscoJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Identifikasi Perkembangan Wilayah Kab - Banjar
Identifikasi Perkembangan Wilayah Kab - Banjar
Diunggah oleh
Iky FransiscoHak Cipta:
Format Tersedia
Riam kanan
Sungai sebagai sentral pengembangan dan pembudayaan perikanan kerambadi sungai
riam kanan
Pertanian aluh aluh gambut
Lahan gambut merupakan salah satu lahan suboptimal yang memiliki
kesuburan rendah, tingkat kemasaman yang tinggi, dan drainase yang buruk. Ciri
utama lahan gambut adalah kandungan karbon minimal 18%, dan ketebalan minimal
50 cm (Nurida, et al., 2011; Sabiham dan Sukarman, 2012). Menurut Masganti dan
Yuliani (2006) gambut berperan penting dalam kelangsungan ekosistem,
mengontrol fungsi-fungsi lingkungan dan biologis yang sangat penting dalam
menjaga kualitas lingkungan.
Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian sudah dilakukan sejak lama,
meskipun belum optimal namun dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan
pangan terhadap masyarakat sekitar. Akan tetapi Lahan gambut sangat
memerlukan pengelolaan yang baik dan penuh kehati-hatian, karena sifatnya yang
rapuh sehingga dapat mengalami degradasi atau penurunan fungsi lahan. Untuk
itu perlu inovasi teknologi yang tepat sehingga lahan gambut dapat dimanfaatkan
untuk pertanian.
Telah diketahui bahwa luas lahan gambut berubah seiring waktu. Luas lahan
gambut di Indonesia menurut Widjaja-Adhi et al. (1992) mencapai 20,9 juta hektar;
Radjagukguk (1995) menyebutkan angka 20,1 juta hektar; Notohadiprawiro (1996)
menyebutkan luas lahan gambut Indonesia tidak lebih dari 17 juta hektar;
Puslittanak (2000) menyatakan bahwa lahan gambut di Indonesia hanya 14,5 juta
hektar dan berdasarkan updating data/peta lahan gambut menurut BBSDLP (2011)
sekitar 14,9 juta ha (Gambar 1).
Dalam pemanfaatannya untuk pertanian, lahan gambut mempunyai
beberapa masalah, yaitu : 1) ketebalan/kedalaman gambut; 2) sifat kering tidak
dapat balik (irreversible drying); 3) kemasaman tanah yang tinggi (pH rendah); 4)
rendahnya tingkat kesuburan, dan 5) pengaturan tata air (Abdurrachman, et al.,
1998).
Menurut Noor, et al. (2013) apabila lahan gambut dimanfaatkan sebagai
kawasan budidaya maupun kawasan lindung atau restorasi, harus dihadapakan
pada berbagai permasalahan yaitu : 1) kerusakan tata hidrologis; 2) degradasi lahan
akibat kebakaran; 3) dampak perubahan iklim; 4) kemiskinan; 5) pembalakan liar,
dan perdagangan karbon. Gambar 2 menunjukkan kerangka keterkaitan antara
pengelolaan lahan gambut dengan permasalahan yang dihadapi. Lahan gambut
yang diusahakan untuk pertanian memerlukan input luar yang tinggi untuk
menanggulangi permasalahan yang dihadapi. Input luar yang diperlukan antara lain
adalah amelioran dan pupuk. Seringkali amelioran dan pupuk yang diberikan hanya
memberikan pengaruh sesaat karena sorption power gambut sangat lemah
terhadap kation maupun anion (Agus dan Subiksa, 2008). Lahan gambut yang
dikelola dengan baik (selalu disiram dan diberi bahan amelioran berupa kapur,
pupuk kandang, abu hasil bakaran gulma , dan jerami sebagai mulsa) dapat
memberikan hasil produktivitas yang cukup tinggi (Simatupang, et al., 2013).
Umumnya tingkat kesuburan tanah gambut dipengaruhi oleh tingkat dekomposisi,
ketebalan, bahan penyusun dan lingkungan pembentukannya (Anwar,
2012).
Pengembangan lahan gambut diartikan sebagai upaya menjadikan lahan
gambut sebagai lahan produktif, yaitu lahan yang menghasilkan atau memproduksi
bahan pangan (padi, palawija), sayuran, hortikultura, perkebunan (karet,kelapa,
kelapa sawit atau sejenisnya) (Noor, 2013). Radjaguguk (2004) menyatakan bahwa
pertanian berkelanjutan di lahan gambut diartikan sebagai suatu pertanian yang
produktif dan menguntungkan, dengan tetap melaksanakan konservasi terhadap
sumberdaya alam, dan mengupayakan menekan dampak negatip pada lingkungan
hidup serendah mungkin
Irigasi martapura
Tahura sultan adam mandiangin
Karang intan batu gunung
Usaha pertambangan yang telah berhenti, baik karena habisnya
cadangan ekonomis maupun karena masalah lainnya, umumnya
meninggalkan bahan galian yang masih memiliki potensi ekonomi pada saat
sekarang maupun masa mendatang. Selain itu usaha pertambangan sering
tidak mengolah bahan galian lain dan mineral ikutan sehingga tidak
memperhatikan peningkatan nilai tambah suatu bahan galian pada suatu
lokasi tambang. Penanganan lahan bekas tambang sering tidak dilakukan
dengan baik dan benar sehingga memberikan potensi penambangan liar,
pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan
kegiatan pemantauan dan pendataan bahan galian pada lokasi bekas
tambang sebagai upaya penerapan aspek konservasi bahan galian.Usaha
pertambangan tanpa izin (PETI)
pada suatu wilayah menyebabkan pengelolaan bahan galian tidak dapat
berlangsung secara
sistematis, aman dan optimal sesuai dengan
kaidah konservasi bahan galian. Evaluasi potensi bahan galian di daerah bekas
tambang dan wilayah PETI belum dapat dilakukan secara maksimal, karena
tidak tersedianya data bahan galian pada kawasan tersebut. Ketidak-lengkapan
data potensi bahan galian di daerah bekas tambang dan wilayah PETI
menyebabkan kurang baiknya perencanaan dan penentuan kebijakan yang
berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan kawasan pertambangan di daerah
tersebut.
Lokasi kegiatan ini berada dalam wilayah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan
Selatan. Posisi geografis terletak antara 114o 30’ 20” - 115o 35’ 37” BT dan 2o
49’ 55” - 3o 43’ 28” LS, dengan luas wilayah
4670 Km2. Pemantauan dan pendataan dilaksanakan dari 27 Agustus 2003 sampai
20
September 2003 di wilayah Kecamatan
Astambul, Mataraman, Simpang Empat, Sungai Pinang dan Karang Intan. Daerah
Banjar ini dapat dicapai dengan perjalanan
udara dengan route Jakarta-Banjarmasin, dilanjutkan dengan
perjalanan darat dari Banjarmasin ke Martapura dan Banjarbaru.
Lokasi-lokasi usaha pertambangan dapat dicapai dari Martapura dan
Banjarbaru melalui jalan darat dengan kendaraan bermotor Di
beberapa lokasi tambang dan PETI, kegiatan penambangan telah
berhenti sehingga petugas tidak menjumpai penambang atau
bekas pemilik usaha pertambangan. Kegiatan PETI dilakukan secara
tidak sistematis sehingga banyak data penambangan yang tidak
didokumentasikan sebelumnya, termasuk data eksplorasi dan
produksi. Oleh karena itu data dan informasi mengenai pelaku usaha,
kualitas batubara, jumlah sumberdaya dan cadangan, mining
recovery, stripping ratio, kapasitas produksi, peralatan tambang dan
pengolahan batubara serta data produksi lainnya tidak dapat
diperoleh secara lengkap dan akurat, dan hanya diperoleh dari
penjelasan masyarakat secara informal dan dari data sekunder
hasil penelitian terdahulu. Kabupaten Banjar memiliki potensi bahan galian yang
cukup baik dan bervariasi,meliputi mineral logam (emas, besi, kromit,nikel, mangan dan
platina), mineral industri (intan, lempung, kaolin, pasir kuarsa, batugamping, marmer dan
batuan beku), batubara dan gambut. Sebagian bahan galian ini telah ditambang baik oleh
masyarakat secara tradisional maupun pengusaha swasta
Anda mungkin juga menyukai
- Bab IiiDokumen12 halamanBab IiiIky FransiscoBelum ada peringkat
- Muhammad Rizki 1810115210009 Lahan Basah Tugas 9 Waduk Dan SawahDokumen5 halamanMuhammad Rizki 1810115210009 Lahan Basah Tugas 9 Waduk Dan SawahIky FransiscoBelum ada peringkat
- Wahyu Ahmad 1Dokumen9 halamanWahyu Ahmad 1Iky FransiscoBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen8 halamanBab IiIky FransiscoBelum ada peringkat
- Saifullah 1810115120005 Parameter Menentukan Kualitas AirDokumen8 halamanSaifullah 1810115120005 Parameter Menentukan Kualitas AirIky FransiscoBelum ada peringkat
- Tugas Nurjannah 7Dokumen10 halamanTugas Nurjannah 7Iky FransiscoBelum ada peringkat
- Freddy Alky Pratama - 1810115110016 - Peta BatimetriDokumen10 halamanFreddy Alky Pratama - 1810115110016 - Peta BatimetriIky FransiscoBelum ada peringkat
- Laporan Bina DesaDokumen12 halamanLaporan Bina DesaIky FransiscoBelum ada peringkat
- Kartu Ujian 18862040021Dokumen1 halamanKartu Ujian 18862040021Iky FransiscoBelum ada peringkat
- Laporan BiosferDokumen20 halamanLaporan BiosferIky FransiscoBelum ada peringkat
- Isi ProposalDokumen33 halamanIsi ProposalIky FransiscoBelum ada peringkat
- Bab V Hasil PenelitianDokumen31 halamanBab V Hasil PenelitianIky FransiscoBelum ada peringkat
- Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang KepariwisataanDokumen8 halamanPerlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang KepariwisataanIky FransiscoBelum ada peringkat
- Atlas Dan Peta NavigasiDokumen7 halamanAtlas Dan Peta NavigasiIky FransiscoBelum ada peringkat
- Muhammad Rajib Adde Riyanto - 1810115310016 - (NDVI, RVI, TVI)Dokumen20 halamanMuhammad Rajib Adde Riyanto - 1810115310016 - (NDVI, RVI, TVI)Iky FransiscoBelum ada peringkat
- Lambang NegaraDokumen12 halamanLambang NegaraIky FransiscoBelum ada peringkat
- PRESIPITASIDokumen20 halamanPRESIPITASIIky FransiscoBelum ada peringkat