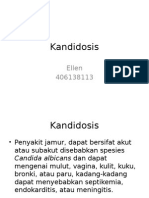HIV
Diunggah oleh
ellenjapJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
HIV
Diunggah oleh
ellenjapHak Cipta:
Format Tersedia
PENDAHULUAN
Di Indonesia, sejak tahun 1999 telah terjadi peningkatan jumlah ODHA pada kelompok
orang berperilaku risiko tinggi tertular HIV yaitu para penjaja seks komersial dan penyalah-
guna NAPZA suntikan di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Riau, Bali, Jawa Barat dan
Jawa Timur sehingga provinsi tersebut tergolong sebagai daerah dengan tingkat epidemi
terkonsentrasi (concentrated level of epidemic). Tanah Papua sudah memasuki tingkat
epidemi meluas (generalized epidemic). Hasil estimasi tahun 2009, di Indonesia terdapat
186.000 orang dengan HIV positif.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan sebanyak 278 rumah sakit
rujukan Odha (Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
780/MENKES/SK/IV/2011 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang
dengan HIV (lihat Lampiran 1)) yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia.
Dari Laporan Situasi Perkembangan HIV & AIDS di Indonesia sampai dengan September
2011 tercatat jumlah Odha yang mendapatkan terapi ARV sebanyak 22.843 dari 33 provinsi
dan 300 kab/kota, dengan rasio laki-laki dan perempuan 3 : 1, dan persentase tertinggi pada
kelompok usia 20-29 tahun.
DEFINISI
Klasifikasi berdasarkan CDC untuk infeksi HIV adalah berdasarkan kondisi klinis terkait
infeksi HIV dan hitung limfosit T CD4+. Setiap orang yang terinfeksi HIV dengan hitung
CD4 <200/L masuk dalam definisi AIDS, tanpa memperhatikan adanya simptom atau infeksi
oportunistik. Apabila individu memilki kondisi klnis pada kategori B, klasifikasi penyakitnya
tidak dapat kembali pada kategori A. Hal yang sama berlaku pada kategori C dan
hubungannya dengan kategori B.
ETIOLOGI
HIV adalah penyebab dari AIDS, virus ini termasuk dalam famili human retroviruses
(Retroviridae) dan subfamili lentivirus. Empat retrovirus yang diketahui dapat menyebabkan
penyakit pada manusia termasuk dalam 2 grup: human T lymphotropic viruses (HTLV)-I dan
HTLV-II, yang merupakan transforming retrovirus; dan human immunodeficiency viruses,
HIV-1 dan HIV-2, yang menyebabkan efek sitopatik (citopathic) baik langsung maupun tidak
langsung. Penyebab HIV terbanyak di seluruh dunia yaitu HIV-1, yang terdiri atas beberapa
subtipe dengan distribusi geografik yang berbeda-beda. Pandemik AIDS secara primer
disebabkan oleh virus HIV-1 grup M.
MORFOLOGI
Mikroskop elektron menunjukkan bahwa struktur virion HIV adalah ikosahedral dan
mengandung duri luar yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh dua protein amplop
utama, eksternal gp120 dan transmembran gp41. Virion bertunas dari permukaan sel yang
terinfeksi menggabungkan berbagai protein host, termasuk antigen MHC (major
histocompatibility complex) kelas I dan II, ke lapisan lipidnya.
B. Structure of HIV-1, including the gp120 envelope, gp41 transmembrane components of
the envelope, genomic RNA, enzymereverse transcriptase, p18(17) inner membrane (matrix),
and p24 core protein (capsid). (Copyright by George V. Kelvin). (Adapted from RC Gallo: Sci
Am 256:46, 1987.)
SIKLUS REPLIKASI HIV
HIV adalah virus RNA dengan karakteristik berupa transkripsi balik dari genom RNA ke
DNA melalui enzim reverse transcriptase. Siklus replikasi dari HIV dimulai dari pengikatan
dengan afinitas tinggi dari preotein gp120 kepada reseptor pada permukaan cell host, yaitu
molekul CD4. Molekul CD4 adalah protein 55-kDA yang banyak ditemukan pada subset
limfosit T yang bertanggung jawap terhadap fungsi helper pada sistem imun. Ini juga
diekspresikan pada permukaan monosit atau makrofag dan dendritik/ sel Langerhans. Setelah
gp120 terikat pada CD4, gp120 mengalami perubahan yang memfasilitasi pengikatan ke satu
atau dua ko-reseptor utama, yaitu CCR5 dan CXCR4. Keduanya termasuk dalam famili dari
7-transmembrane-domain protein G, coupled cellular receptors, dan penggunaan satu atau
kedua reseptor ini merupakan tempat masuk ke dalam sel, yang merupakan determinan
penting untuk cellular tropism dari virus.
Beberapa sel dendritik mengekspresikan bermacam lectin tipe-C reseptor pada
permukaannya, salah satunya bernama DC-SIGN, yang juga berikatan dengan afinitas tinggi
kepada protein amplop HIV gp120, sehingga sel dendritik juga memfasilitasi pengikatan
virus kepada sel T CD4+.
Setelah pengikatan protein amplop ke molekul CD4, fusi dengan membran sel host terjadi
melalui penetrasi molekul gp41 ke membran plasma dari sel target dan selanjutnya
menggulung dirinya untuk menggabungkan virion dan membran plasma.
Setelah fusi, kompleks preintegrasi yang tediri dari viral RNA dan viral enzim yang
dikelilingi oleh kapsid protein, dilepas ke dalam sitoplasma dan sel target. Kompleks ini
kemudian melintasi sitoplasma untuk mencapai nukleus. Enzim reverse transcriptase
mengkatalisasi transkripsi dari genomik RNA ke DNA, dan mantel protein terbuka untuk
melepas hasilnya berupa double-strand proviral HIV-DNA.
Pada tahap ini, genome virus sangat rentan terhadap faktor selular yang dapat menghambat
progresitas dari infeksi. Baru-baru ini protein selular yang termasuk famili APOBEC dapat
menghambat progresitas infeksi virus segera setelah virus memasuki sel. Protein APOBEC
berikatan dengan reverse transcripts dan melakukan deaminasi viral cytidine, sehingga
terjadi hipermutasi dari genom HIV. Namun sekarang HIV telah mempunyai strategi khusus
untuk melindungi dirinya dari APOBEC. Protein viral Vif mentargetkan APOBEC untuk
degradasi proteasomal.
TRANSMISI
HIV ditransmisikan secara primer oleh kontak seksual (baik heteroseks dan sesama pria),
darah dan prodaknya, dan oleh ibu terinfeksi kepada janinnya intrapartum, perinatal, atau
melalui air susu ibu. Setelah 30 tahun penelitian, tidak ada bukti bahwa HIV ditransmisikan
melalui kontak kasual atau bahwa virus dapat menyebar melalui serangga, seperti gigitan
nyamuk.
TRANSMISI SEKSUAL
Infeksi HIV sebagian besar adalah penyakit menular seksual (PMS) di seluruh dunia. Sejauh
ini mode penularan yang paling umum, terutama di negara berkembang, adalah transmisi
heteroseksual, walaupun pada negara barat transmisi seksual antar laki-laki juga terjadi.
HIV telah didemonstrasikan di cairan seminal baik dalam sel mononuklear yang terinfeksi
dan pada sel yang tidak terinfeksi. Virus ini terkonsentrasi di cairan seminal, terutama pada
situasi dimana terdapat peningkatan jumlah limfosit dan monosit pada cairan, pada inflamasi
genital seperti uretritis dan epididimitis, kondisi yang terkait PMS. Virus juga ditemukan
pada hapusan servikal dan cairan vagina. Terdapat peningkatan risiko transmisi HIV terkait
unprotected receptive anal intercourse (URAI) pada pria dan wanita dibandingkan risiko
terkait receptive vaginal intercourse, karena hanya membran mukosa rektal yang tipis dan
rentan yang memisahkan semen dari sel yang rentan di mukosa, dan trauma mungkin
dihubungkan dengan anal intercourse. Anal douching dan praktek seksual yang membuat
mukosa rektal trauma juga meningkatkan risiko infeksi. Anal intercourse mempunyai 2
modalitas dalam infeksi : (1) inokulasi langsung terhadap darah yang dikarenakan robekan
traumatik pada mukosa, dan (2) infeksi terhadap sel target yang rentan, seperti sel
Langerhans, di lapisan mukosa.
Diantaran banyaknya faktor lain yang ditemukan dalam studi transmisi HIV, keadaan
terdapatnya PMS berhubungan kuat dengan transmisi HIV. Dalam keadaan ini, ada hubungan
erat antara ulserasi genital dan transmisi. Infeksi mikroorganisme seperti Treponema
pallidum, Haemophilus ducreyi, dan herpes simplex virus adalah sebab penting dari ulserasi
genital yang dihubungkan dengan transmisi HIV. Disamping itu, patogen yang bertanggung
jawap atas PMS non-ulseratif yang disebabkan Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae, dan Trichomonas vaginalis juga berhubungan dengan peningkatan risiko infeksi
HIV.
Studi menjelaskan bahwa manfaat dari sirkumsisi pada pria mungkin dihubungkan dengan
rentannya pria yang tidak di sirkumsisi terhadap PMS ulseratif, juga faktor lain seperti
mikrotrauma terhadap foreskin dan glans penis. Sebagai tambahan, kulit luar mengandung sel
Langerhans yang banyak dan sel CD4, makrofag, serta target selular lain untuk HIV.
Pada studi mengenai penggunaan kontrasepsi oral dihubungkan dengan peningkatan infeksi
HIV, yang tidak terjadi pada penggunaan kondom untuk mengontrol kehamilan. Fenomena
ini mungkin dikarenakan pengaruh obat terhadap mukosa servikal, sehingga lebih mudah
terpajan virus.
Seks oral merupakan mode transmisi HIV yang lebih tidak efisien dibanding melalui anal
atau vaginal.
Hubungan dengan konsumsi alkohol dan obat terlarang dihubungkan dengan perlaku seksual
yang tidak aman sehingga meningkatkan risiko penularan seksual HIV. Methamphetamine
dan obat lain (ekstasi, ketamine, gamma hydrocybutyrate) yang diminum bersama sildenafil
(Viagra), tadalfil (Cialis), dihubungkan dengan praktek seksual berisiko dan peningkatan
risiko HIV
TRANSMISI DARAH DAN PRODUKNYA
HIV dapat ditransmisikan kepada individu yang menerima transfusi darah dari orang dengan
HIV, produk darah, atau jaringan transplantasi maupun pengguna jarum suntik yang terkena
HIV saat memakai alat suntikan bersama. Transmisi parenteral HIV saat injeksi obat tidak
memerlukan tusukan IV; SC maupun IM dapat menularkan HIV walaupun ada yang
mengatakan bahwa risikonya lebih rendah.
Sekarang ini di Amerika dan negara maju lainnya, telah dilakukan beberapa hal yang
menurunkan risiko transmisi infeksi HIV melalui transfusi darah dan prodaknya, antara lain
skrining antibodi HIV untuk donasi darah, antigen p24 HIV, dan asam nukleat HIV.
TRANSIMISI MELALUI PEKERJAAN: PELAYANAN KESEHATAN,
LABORATORIUM
Terdapat risiko penularan HIV melalui pekerjaan kepada pekerja layanan kesehatan dan
laboratorium yang berhubungan dengan materi yang mengandung HIV, terutama apabila
benda tajam digunakan. Terdapat 600,000 hingga 800,000 pekerja pelayanan kesehatan yang
terkena jarum atau benda medis tajam lainnya di Amerika setiap tahunnya. Pajanan yang
menempatkan pekerja pelayanan kesehatan pada risiko terkan infeksi HIV adalah trauma
perkutaneus (contoh, terkena jarum atau benda tajam) atau kontak dengan membran mukosa
atau kulit yang non-intak (contoh, kulit yang pecah-pecah, terabrasi, atau dengan dermatitis)
dengan darah, jaringan, atau cairan tubuh infeksius lainnya.
Studi menunjukan bahwa risiko tertularnya HIV dari tusukan kulit melalui jarum atau benda
tajam yang terkontaminasi dengan darah dari orang dengan infeksi HIV adalah 0.3% dan
dengan pajanan membran mukosa adalah 0.09% apabila orang yang terkena tidak diberikan
obat antiretroviral dalam 24 jam pertama. Seluruh luka tusuk dan pajanan membran mukosa
dari orang dengan infeksi HIV telah diberikan pengobatan profilaksis dengan combination
antiretroviral therapy (cART). Praktik ini telah menurunkan insidens penularan HIV melalui
tusukan pada pelayanan kesehatan.
Selain itu, cairan semen dan vagina juga sangat infeksius, namun tidak digolongkan dalam
transmisi okupasi dari pasien kepada pekerja kesehatan. Berikut ini juga merupakan cairan
yang terbilang infeksius: cairan serebrospinal, cairan sinovial, cairan pleura, cairan
peritoneal, cairan perkardial, dan cairan amnion. Feses, sekresi nasal, saliva, sputum,
keringat, air mata, urin, dan vomitus tidak termasuk yang infeksius, kecuali apabila terdapat
darah.
TRANSMISI MATERNAL-FETAL
Infeksi HIV dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada janinnya semasa kehamilan,
persalinan, atau saat meyusui. Analisa virologik terhadap fetus yang diaborsi menunjukan
bahwa HIV dapat ditularkan kepada janin selama trimester pertama atau kedua saat
kehamilan. Namun, transmisi maternal kepada janin terjadi paling banyak pada periode
perinatal. Studi di Rwanda dan Zaire menunjukan perbandingan transmisi ibu ke anaknya
yaitu 23-30% sebelum kelahiran, 50-65% saat persalinan, dan 12-20% saat menyusui.
Dengan tidak adanya terapi profilaksis antiretroviral kepada ibu saat kehamilan, persalinan,
dan kepada fetus setelah kelahiran, probabilitas transmisi HIV dari ibu ke janin/ bayi
bervariasi dari 25 hingga 35% pada negara maju dan 15 hingga 25% pada negara maju.
Variasi ini berdasarkan ketersediaan perawatan prenatal juga stadium HIV dan keadaan
kesehatan umum ibu selama kehamilan. Angka tinggi pada transmisi telah dilaporkan
berhubungan dengan banyak faktor, salah satunya adalah tingkat maternal yang tinggi pada
plasma viremia. Pada sebuah studi pada 552 kehamilan di Amerika, angka transmisi ibu ke
bayi adalah 0% pada wanita dengan <1000 HIV RNA per mililiter darah, 16.6% pada wanita
dengan 1000-10.000 copies/mL, 21.3% pada wanita dengan 10.001-50.000 copies/mL, 30.9%
pada wanita dengan 50.001-100.000 copies/mL, dan 40.6% pada wanita dengan >100.000
copies/mL. Hitung sel T CD4+ yang rendah juga dihubungkan dengan angka penularan yang
tinggi.
Perpanjangan waktu interval antara ruptur membran dan persalinan merupakan faktor risiko
lain untuk penularan. Keadaan lain yang merupakan faktor risiko potensial, adalah
korioamnionitis pada persalinan, penyakit menular seksual saat kehamilan, penggunaan obat-
obatan selama kehamilan, merokok, persalinan preterm, dan prosedur obstetri seperti
amniosentesis, amnioskopi, episiotomi.
Pada studi seminal yang diadakan di Amerika dan Perancis pada 1990, zidovudine yang
diberikan pada wanita hamil dengan HIV sejak awal trimester kedua hingga persalinan dan
pada bayi selama 6 minggu setelah kelahiran, secara signifikan menurunkan angka penularan
HIV intrapartum dan perinatal dari 22.6% hingga kurang dari 5%. Sekarang, angka penularan
ibu kepada anak telah turun hingga 1% kurang pada wanita hamil yang menerima terapi
antiretroviral kombinasi untuk infeksi HIV-nya.
Pada negara berkembang, rekomendasi untuk menurunkan penularan HIV perinatal termasuk
diantaranya uji HIV secara volunter dan konseling pada wanita hamil, profilaksis
antiretroviral dengan satu atau lebih obat, manajemen obstetri untuk meminimalkan pajanan
darah maternal dan sekret genital kepada bayi, dan menghindarkan menyusui.
Menyusui merupakan modalitas penting dalam transmisi infeksi HIV pada negara
berkembang, terutama apabila ibu menyusui anaknya untuk waktu yang lama. Faktor risiko
untuk transmisi ibu kepada anak melalui menyusui masih belum dimengerti. Faktor yang
meningkatkan transmisi antara lain HIB yang terdeteksi dalam air susu ibu, kondisi mastitis,
hitung sel T CD4+ yang rendah, dan defisiensi maternal vitamin A. Risiko penularan HIV
melalui menyusui tertinggi pada bulan-bulan awal menyusui. Pada negara maju, menyusui
pada wanita terinfeksi harus dihindari. Namun, ada ketidaksetujuan pada negara berkembang
dimana air susu ibu merupakan satu-satunya nutrisi adekuat dan juga sebagai imunitas
melawan infeksi non-HIB pada bayi. Pendekatan optimal untuk mencegah penularan pada ibu
yang memilih untuk tetap menyusui adalah memberikan terapi kontinu pada ibu yang
terinfeksi. Pendekatan ini mudah dicapai dengan adanya cART pada negara maju.
TRANSMISI MELALUI CAIRAN TUBUH
Walaupun HIV dapat diisolasi dengan titer rendah dari saliva orang yang terinfeksi, tidak ada
bukti bahwa saliva dapat menularkan infeksi HIV, baik melalui ciuman maupun paparan lain.
Saliva mengandung faktor antiviral endogen; diantara faktor ini, HIV spesifik imunoglobulin
IgA, IgG, dan IgM dapat dideteksi pada sekresi saliva orang yang terinfeksi.
It has been suggested that large glycoproteins such as mucins and thrombospondin 1
sequester HIV into aggregates for clearance by the host. In addition, a number of soluble
salivary factors inhibit HIV to various degrees in vitro, probably by targeting host cell
receptors rather than the virus itself. Perhaps the best studied of these, secretory leukocyte
protease inhibitor (SLPI), blocks HIV infection in several cell culture systems, and it is found
in saliva at levels that approximate those required for inhibition of HIV in vitro. In this
regard, higher salivary levels of SLPI in breast-fed infants were associated with a decreased
risk of HIV transmission through breast milk. It has also been suggested that submandibular
saliva reduces HIV infectivity by stripping gp120 from the surface of virions, and that saliva-
mediated disruption and lysis of HIV-infected cells occurs because of the hypotonicity of oral
secretions. There have been outlier cases of suspected transmission by saliva, but these have
probably been blood-to-blood transmissions. Transmission of HIV by a human bite can occur
but is a rare event. In addition, a most unusual form of HIV transmission from infected
children to mothers in the former Soviet Union has been identified. In those cases, the
children (infected through transfusion) were said to have bleeding sores in the mouth, and the
mothers were said to have lacerations and abrasions on and around the nipples of the breast
resulting from trauma from the children's teeth. Breast-feeding had been continued until the
children were older than is usual in other developed countries.
Although virus can be identified, if not isolated, from virtually any body fluid, there is no
evidence that HIV transmission can occur as a result of exposure to tears, sweat, or urine.
However, there have been isolated cases of transmission of HIV infection by body fluids that
may or may not have been contaminated with blood. Most of these situations occurred in the
setting of a close relative providing intensive nursing care for an HIV-infected person without
observing universal precautions, underscoring the importance of adhering to such precautions
in the handling of body fluids and wastes from HIV-infected individuals.
PATOFISIOLOGI DAN PATOGENESIS
Penyakit HIV adalah keadaan imunodefisiensi berat yang dikarenakan defisiensi progresif
dari limfosit T baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Subset helper dari limfosit T
terdapat pada permukaan molekul CD4, yang merupakan reseptor selular utama untuk HIV.
Ko-reseptor harus hadir bersama dengan CD4 untuk pengikatan, fusi, dan masuknya HIV-1
ke dalam taget sel. HIV menggunakan dua ko-reseptor utama, yaitu CCR5 dan CXCR4,
untuk fusi dan masuknya virus. Beberapa mekanisme untuk deplesi selular dan/ atau
disfungsi imun dari sel T CD4+ telah dijelaskan secara in vitro, termasuk diantaranya infeksi
dan destruksi langsung sel-sel ini oleh HIV, juga efek indirek seperti clearance imun terhadap
sel yang terinfeksi, kelelahan imun karena aktivasi selular, dan activation-induced cell death.
Pasien dengan jumlah sel T CD4 di bawah normal memiliki risiko tinggi terhadap berbagai
infeksi oportunistik.
Kombinasi dari kejadian patogen virus dan imunopatogenik yang terjadi selama penyakit
HIV mulai dari infeksi inisial (primer) hingga tahap akhir merupakan hal yang kompleks dan
bervariasi. Pada pasien yang tidak diterapi atau yang terapinya tidak adekuat, dalam hitungan
tahun, hitung sel T CD4+ turun hingga dibawah 200/L dan pasien menjadi sangat rentan
terhadap infeksi oportunistik. Untuk alasan ini, CDC memberi definisi AIDS terhadap semua
individu dengan infeksi HIV dengan hitung sel T CD4+ di bawah jumlah tersebut. Pasien
mungkin mengalami gejala dan tanda konstitusional dan mungkin mengalami infeksi
oportunistik. Sangat umum bahwa sel T CD4+ turun hingga 10/L atau bahkan nol. Pada
negara dimana cART dan profilaksis dan terapi untuk infeksi oportunistik tersedia,
kelangsungan hidup meningkat bahkan pada pasien dengan penyakit HIV stadium lanjut.
Jaringan limfoid merupakan tempat anatomi utama untuk infeksi HIV. Walaupun pengukuran
plasma viremia untuk menentukan tingkat aktivitas penyakit, replikasi virus terjadi terutama
pada jaringan limfoid dan tidak di darah. Jumlah plasma viremia menunjukan produksi virus
pada jaringan limfoid. Limfadenopati menunjukan aktivitas selular dan respon imun terhadap
virus pada jaringan limfoid, yang memiliki karakter berupa hiperplasia folikuler atau
germinal.
Events that transpire from primary HIV infection through the establishment of chronic
persistent infection to the ultimate destruction of the immune system. See text for details.
CTLs, cytolytic T lymphocytes; GALT, gut-associated lymphoid tissue.
AKTIVASI IMUN, INFLAMASI, DAN PATOGENESIS HIV
Aktivasi sistem imun dan tingkat inflamasi merupakan komponen penting dalam respon imun
terhadap antigen asing. Aktivasi imun dan inflamasi pada individu terinfeksi HIV memberi
kontribusi pada (1) replikasi HIV, (2) induksi disfungsi imun, dan (3) peningkatan insiden
kondisi kronis yang berkaitan dengan aktivasi imun persisten dan inflamasi, yaitu: sindrom
aging, fragilitas tulang, kanker, penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit ginjal, penyakit
hati, dan disfungsi neurokognitif.
Sistem imun normalnya berada dalam keadaan homeostasis, menunggu gangguan dari
stimulus antigen asing. Apabila respon imun bereaksi dan menyingkirkan antigen, sistem ini
akan kembali dalam keadaan tenangnya. Namun pada kasus infeksi HIV, replikasi virus
menetap dan aktivasi imun persisten. Replikasi HIV paling efisien terdapat pada sel T CD4+;
pada infeksi HIV, aktivasi kronik membuat substrat sel menjadi penting untuk replikasi virus
sepanjang perjalanan penyakit HIV.
Sebagai tambahan terhadap faktor endogen seperti sitokin, faktor eksogen seperti mikroba
yang berhubungan dengan peningkatan aktivitas selular dapat meningkatkan repliaksi HIV
dan karenanya memiliki efek penting dalam patogenesis HIV. Ko-infeksi dengan virus seperti
HSV tipe 1 dan 2, cytomegalovirus, human herpesvirus, epstein-barr virus, HBV, adenovirus,
dan HTLV-1 telah menunjukan peningkatan ekspresi HIV. Dua penyakit global, malaria dan
tuberkulosis telah menunjukan peningkatan viral load HIV. Mycobacterium tuberculosis
merupakan infeksi oportunistik paling banyak pada individu dengan infeksi HIV.
TRANSLOKASI MIKROBIAL DAN AKTIVASI IMUN PERSISTEN
Salah satu mekanisme dari aktivasi imun yang persisten melibatkan disrupsi dari barier
mukosa di usus dan jaringan limfoid submukosa karena replikasi HIV. Sebagai hasilnya,
terdapat peningkatan lipopolisakarida (LPS) dari bakteri yang berpindah dari lumen usus ke
mukosa yang rusak menuju ke sirkulasi, menyebabkan aktivasi sistem imun persisten dan
inflamasi. Efek ini dapat menetap bahkan ketika HIV viral load <50 kopi/mL oleh cART.
Keadaan aktif dari infeksi HIV ditandai dengan hiperaktivasi dari sel B yang menyebabkan
hipergammaglobulinemia; peningkatan turnover limfosit; aktivasi monosit; ekspresi dari
aktivasi marker pada sel T CD4 dan CD8; peningkatan apoptosis selular; hiperplasia kelenjar
limfe; peningkatan sekresi sitokin proinflamasi terutama IL-6; peningkatan CRP, fibrinogen,
d-dimer; dan fenomena autoimun.
Dengan penggunaan luas dari terapi antiretroviral, sebuah immune reconstitution
inflammatory syndrome (IRIS) telah dilaporkan meningkat. IRIS merupakan sebuah
autoimmune-like phenomenon yang memiliki karakteristik berupa penurunan kondisi klinis,
biasanya digolongkan dalam sistem organ tertentu, pada individu yang telah memulai cART.
Hal ini berhubungan dengan penurunan viral load dan pemulihan sebagian sistem imun, yang
biasa ditandai dengan peningkatan sel T CD4+. Imunopatogenesis dari kejadian ini
dihubungkan dengan peningkatan respon imun terhadap kehadiran dari antigen residual yang
biasanya merupakan mikrobial dan biasa terjadi karena Mycobacterium tuberculosis dan
kriptokokosis.
PERANAN SITOKIN DALAM PATOGENESIS HIV
Sistem imun secara homeostatis diatur oleh sitokin imunoregulator. Sitokin yang
menginduksi atau meningkatkan ekspresi HIV termasuk diantaranya IL-1, IL-2, IL-3, IL-6,
IL-12, IL-18, TNF-, TNF-, makrofag colony-stimulating factor (M-CSF), dan granulosit-
makrofag colony-stimulating factor (GM-CSF). IL-18 telah memperlihatkan peran dalam
pembentukan sindrom lipodistrofi terkait HIV. Diantara sitokin ini, sitokin proinflamasi
TNF-, IL-1, dan IL-6 merupakan inducer paling poten dalam ekspresi HIV. IFN dan ,
juga IL-32 menekan replikasi HIV, dimana transfroming growth factor (TGF) , IL-4, IL-10,
dan IFN- dapat menekan ataupun meningkatkan ekspresi HIV, tergantung sistem yang
terlibat. IL-27 menekan replikasi HIV dengan mempengaruhi gen terkait IFN. CC-
chemokines RANTES (CCL5), macrophage inflammatory protein (MIP) 1 (CCL3), dan MIP-
1 (CCL4) menghambat infeksi dan penyebaran dari R5 HIV-1 strain, sedangkan stromal cell
derived factor (SDF) 1 menghambat infeksi dan penyebaran dari strain X4. Famili alpha
defensin dari sitokin telah memperlihatkan menghambat baik virus R5 maupun X4.
Mekanisme molekuler dari regulasi HIV yang paling dimengerti adalah TNF-, yang
mengaktivasi protein NF-B yang berfungsi sebagai aktivator transkripsional untuk ekspresi
HIV. HIV-inducing effect dari IL-1 diduga berlangsung pada tahap trakskripsi viral yang
terdapat pada NF-B independent manner. IL-6, GM-CSF, dan IFN- meregulasi ekspresi
HIV dengan mekanisme posttranskripsional. Peningkatan TNF- dan IL-6 ditemukan pada
plasma dan cerebrospinal fluid (CSF), dan peningkatan ekspresi dari TNF-, IL-1, IFN-, dan
IL-6 ditemukan pada kelenjar limfe pada individu dengan HIV.
Mekanisme dimana CC-chemokines RANTES (CCL5), MIP-1 (CCL3), dan MIP-1 (CCL4)
menghambat infeksi dari R5 strains HIV, atau SDF-1 menghambat X4 strains melibatkan
hambatan dari pengikatan virus kepada ko-reseptornya, CC-chemokine receptor CCR5 dan
CXC-chemokine receptor CXCR4.
PERAN RESEPTOR DAN KO-RESEPTOR VIRAL
HIV-1 menggunakan dua ko-reseptor utama bersama dengan CD4 untuk berikatan, berfusi,
dan memasuki target sel; ko-reseptor ini adalah CCR5 dan CXCR4, yang juga merupakan
reseptor untuk beberapa kemokin endogen. Strain dari HIV yang menggunakan CCR5
sebagai ko-reseptor adalah virus R5. Strain yang menggunakan CXCR4 adalah virus X4.
Banyak strain virus yang merupakan dual tropic dimana mereka menggunakan keduanya,
disebut R5X4 viruses.
Ligan kemokin untuk ko-reseptor HIV dapat menghambat HIV. Misalnya, CC-chemokines
RANTES (CCL5), MIP-1 (CCL3), dan MIP-1 (CCL4) menghambat infeksi dari R5 strains
HIV, atau SDF-1 menghambat X4 strains.
TARGET SELULAR HIV
Walaupun limfosit T CD4 merupakan taget utama dari HIV, semua sel yang
mengekspresikan molekul CD4 bersama dengan molekul ko-reseptor dapat menjadi target
HIV. Sel dendritik yang bersirkulasi telah dilaporkan mengekspresikan CD4 dalam jumlah
rendah, dan tergantung tingkat maturasinya, sel-sel ini dapat terinfeksi dengan HIV. Sel
langerhans epidermal mengekspresikan CD4 dan dapat terinfeksi HIV in vivo, walaupun
telah diperlihatkan secara in vivo untuk sel dendritik, FDCs, dan sel B, sel ini biasanya
mengikat dan mentransfer virus untuk mengaktifkan sel T CD4, dibandingkan dengan
terinfeksi.
ABNORMALITAS DARI SEL MONONUKLEAR
SEL T CD4+
Lesi imunopatologik utama dari infeksi HIV melibatkan sel T CD4. Pada HIV tingkat lanjut,
defek imun yang dapat dijelaskan adalah deplesi kuantitatif dari se; T CD4+. Namun,
disfungsi sel T dapat terjadi pada pasien di awal infeksi, walaupun hitung sel T CD4+ masih
dalam batas rendah-normal. Salah satu dari abnormalitas awal yang dapat dideteksi adalah
defek dalam respon untul recall antigen, seperti tetanus toksoid dan influenza. Defek dari sel
memori sentral merupakan komponen penting dalam imunopatogenesis HIV.
Kehilangan polifungsional dari sel T CD4+ spesifik HIB, terutama yang memproduksi IL-2,
terjadi pada awal penyakit. Kehilangan dari IL-2 ini dikaitkan dengan penurunan kapasitas
untuk meregulasi ligan CD40, yang juga berpengaruh dalam disregulasi fungsi sel B dalam
penyakit HIV. Abnormalitas lain termasuk kelainan ekspresi dari reseptor IL-2, defektivitas
produksi IL-2, penurunan ekspresi reseptor Il-7 dan penurunan sel T CD4 yang
mengekspresikan CD28, sebuah molekul ko-stimulator yang penting untuk aktivasi sel T. Sel
yang kurang ekspresinya terhadap CD28 tidak dapat berespon secara normal terhadap
aktivasi sinyal.
Disfungsi sel T CD4+ merupakana hasil dari kombinasi deplesi sel karena infeksi langsung
dan efek tidak langsung pada sel.
Respon imun humoral dan selular terhadap HIV memberikan proteksi imunitas dengan cara
eliminasi virus dan sel yang terinfeksi virus. Namun, karena target utama infeksi HIV adalah
sel imunokompeten, respon ini mungkin menyebabkan deplesi sel imun dan disfungsi
imunologik dengan cara mengeliminasi baik sel yang terinfeksi maupun sel innocent
bystander.
Amplop glikoprotein HIV gp120 dan gp160 memilki ikatan dengan afinitas tinggi pada CD4
dan juga reseptor kemokin lainnya. Sinyal intraselular yang ditransduksi oleh gp120 melalui
CD4 dan CCR5/CXCR4 telah dihubungkan dengan berbagai proses imunopatogenik sepeti
anergi, apoptosis, dan abnormalitas dari cell traficking.
Penurunan dari sel T CD4 yang terjadi pada infeksi HIV dikarenakan inabilitas sistem imun
untuk regenerasi dari waktu terjadinya turnover sel T CD4 untuk mengkompensasi baik
kehilangan sel karena HIV maupun karena sebab alami. Setidaknya ada dua mekanisme
utama yang berhubungan dengan kegagalan pool sel T CD4 untuk rekonstitusi secara adekuat
dalam infeksi HIV. Yang pertama karena destruksi sel prekursor limfoid, termasuk thymic
dan sel progenitor sumsum tulang belakang. Keuda karena disrupsi gradual dari jaringan
limfoid yang penting untuk regenerasi sel imunokompeten.
SEL T CD8+
Limfositosis relatif sel T CD8+ berhubungan dengan level tinggi HIV plasma viremia dan
menunjukan disregulasi homeostasis yang berhubungan dengan aktivasi imun. Pada stadium
lanjut HIV, terdapat penurunan signifikan dari sel T CD8+. Penyebab hilangnya aktivitas
sitolitik masih belum jelas, walaupun gangguan fungsional mungkin berhubungan dengan
infeksi HIV dan perjalanan pernyakitnya.
SEL B
Defek predominan pada sel B individu dengan infeksi HIV merupakan salah satu aktivasi
selular yang menyimpang, yang ditandai dengan proliferasi spontan dan sekresi
imunoglobulin dan peningkatan sekresi TNF- dan IL-6.
Defek sel B mempunyai pengaruh pada penurunan respon terhadap vaksinasi dan
peningkatan infeksi bakteri yang dapat ditemukan pada stadium lanjut HIV pada dewasa. Sel
B yang bersirkulasi dapat terdepresi pada infeksi HIV; fenomena ini menunjukan
peningkatan apoptosis dan redistribusi sel keluar dari sirkulasi ke jaringan limfoid, fenomena
yang berhubungan dengan replikasi virus.
MONOSIT/ MAKROFAG
Monosit yang bersirkulasi biasanya normal pada infeksi HIV. Monosit mengekspresikan
molekul CD4 dan beberapa ko-reseptor untuk HIV pada permukaannya, termasuk CCR5,
CXCR4, dan CCR3, dan lainnya yang merupakan target infeksi HIV.
Sel monosit memilki peran untuk diseminasi HIV pada tubuh dan bertindak sebagai reservoir
untuk infeksi HIV, menyebabkan kesulitan baru untuk eradikasi HIV dengan obat
antiretroviral. Makrofag jaringan merupakan sumber penting dari HIV selama respon
inflamasi yang berhubungan dengan infeksi oportunistik. Infeksi dari prekursor monosit pada
sumsum tulang belakang juga memiliki efek terhadap abnormalitas hematologik pada
individu dengan infeksi HIV.
SEL DENDRITIK DAN LANGERHANS
Sel dendritik (DC) memiliki peran penting dalam inisiasi infeksi HIV, yaitu kemampuan HIV
utnuk berikatan dengan reseptor permukaan sel C-type lectin, terutama DC-SIGN. Hal ini
menyebabkan presentasi virus kepada sel target sel T CD4+ menjadi terinfeksi dan terjadi
replikasi virus.
Sel dendritik dibagi menjadi dua yaitu myeloid (mDC) dan plasmacytoid (pDC). pDC
merupakan komponen penting dalam sistem imun innate dan mensekresi jumlah besar dari
IFN- sebagai respon terhadap infeksi virus. Jumlah pDC yang bersirkulasi menurun pada
infeksi HIV walaupun mekanismenya masih belum jelas.
NATURAL KILLER CELLS
Peran dari sel NK adalah menyediakan imunosuveilans terhadap sel terinfeksi virus, sel
tumor, dan sel allogeneic. Abnormalitas fungsional sel NK telah diobservasi pada penyakit
HIV, dan keparahan dari abnormalitas ini meningkat seiring perjalanan peyakit. Dilaporkan
bahwa gangguan sinyal dari sel NK meningkatkan kerentanan terhadap apoptosis. Infeksi
HIV pada target sel men-downregulates HLA-A dan B, namun tidak HLA-C dan D; ini
menjelaskan tentang ketidakmampuan sel NK untuk membunuh sel target yang terinfeksi
HIV.
RESPON IMUN TERHADAP HIV
Mengikuti inisial viremia pada infeksi primer, individu dengan infeksi HIV memiliki
ketahanan respon imun yang pada umumnya membatasi level viremia plasma dan
berkontribusi terhadap delaying dari klinis penyakit selama rata-rata 10 tahun pada individu
yang tidak diobati. Respon imun ini memilki elemen baik imunitas humoral dan cell-
mediated yang melibatkan innate dan adaptive respon imun. Ini diarahkan pada determinan
antigenik pada virion HIV juga pada protein viral yang diekspresikan pada permukaan sel
yang terinfeksi.
RESPON IMUN HUMORAL
Antibodi terhadap HIV biasanya muncul pada 3-6 minggu hingga 12 minggu setelah infeksi
primer. Deteksi terhadap antibodi ini didapatkan pada skrining tes diagnostik untuk infeksi
HIV. Munculnya antibodi HIV yang dapat dideteksi oleh ELISA dan Western blot assay
terjadi karena munculnya antibodi untuk netralisasi; ini muncul mengikuti penurunan inisial
dari plasma viremia, yang berhubungan dengan munculnya limfosit T CD8+ spesifik HIV.
Sementara antibodi terhadap multipel antigen HIV diproduksi, fungsi dari antibodi ini masih
belum jelas. Satu-satunya protein viral yang memperoleh antibodi adalah protein envelope
gp120 dan gp41. Antibodi ini memiliki karakteristik sebagai proteksi dan memilki kontribusi
terhadap patogenesis penyakit HIV. Dalam 6 bulan pertama infeksi, antibodi netralisasi
muncul; namun, virus dengan cepat berhasil lolos dari antibodi ini. Salah satu mekanisme
lolosnya imun ini adalah adanya tambahan dari N-linked glycosylation sites. Tambahan
karbohidrat mengganggu pengenalan envelope oleh antibodi ini.
Sebagai tambahan dari perannya sebagai perlindungan host, antibodi spesifik HIV juga
berpengaruh terhadap patogenesis penyakit. Antibodi terhadap gp41, ketika dalam titer
rendah, telah memperlihatkan secara in vitro mampu memfasilitasi infeksi sel melalui
mekanisme Fc reseptor-mediated yang dikenal sebagai antibody enhancement. Anti-gp120
antibodi yang berpartisipasi dalam ADCC killing dari sel terinfeksi HIV juga membunuh sel
T CD4+ yang tidak terinfeksi apabila sel ini berikatan dengan free gp120, fenomena yang
dinamakan bystander killing.
RESPON IMUN SELULAR
Sel imun T dibagi menjadi dua kategori utama: yang dimediasi oleh helper/ inducer sel T
CD4+, dan yang dimediasi oleh cytotoxic/ immunoregulatory sel T CD8+.
Sel T CD4+ spesifik HIV dapat dideteksi pada mayoritas penderita HIV melalui penggunaan
flow cytometry untuk mengukur produksi sitokin intraselular sebagai respon terhadap MHC
kelas II tetramers atau melalui proliferasi limfosit assay menggunakan HIV antigen seperti
p24. Sel ini memiliki peran penting dalam respon imun kepada HIV dengan cara
menyediakan bantuan kepada sel B spesifik HIV dan sel T CD8+. Sel ini juga mampu
membunuh langsung sel terinfeksi HIV.
Sel T CD4+ merupakan target infeksi HIV oleh antigen-presenting cell selama terbentuknya
respon imun terhadap HIV. Sel T CD8+ spesifik HIV telah ditemukan pada darah perifer
pasien dengan infeksi HIV-1. Limfosit T CD8+ ini melalui reseptor antigen spesifik HIV,
berikatan dan menyebabkan destruksi litik dari target sel. Selain ini sel T CD8+ memiliki
kemampuan mengekspresikan sitoikin, seperti IFN- yang juga muncul dalam infeksi HIV-1.
Setidaknya ada tiga bentuk cell-mediated immunity yang terdapat pada HIV: supresi sel T
CD8+ karena replikasi HIV, ADCC, dan aktivitas sel NK. CD8+ T cellmediated
suppression of HIV replication menunjukan kemampuan sel T CD8+ dari pasien terinfeksi
HIV untuk menghambat replikasi HIV pada kultur jaringan. ADCC, dalam hubungannya
dengan imunitas humoral, terlibat dalam membunuh HIV-expressing cells oleh sel NK
dengan antibodi spesifik melawan antigen HIV. Sedangkan sel NK menunjukkan
kemampuan untuk membunuh sel target yang terinfeksi HIV pada kultur jaringan.
DIAGNOSIS
Program penanggulangan AIDS di Indonesia mempunyai 4 pilar, yang semuanya menuju
pada paradigma Zero new infection, Zero AI DS-related death dan Zero Discrimination.
Empat pilar tersebut adalah:
1. Pencegahan (prevention); yang meliputi pencegahan penularan HIV melalui transmisi
seksual dan alat suntik, pencegahan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan,
pencegahan HIV dari ibu ke bayi (Prevention Mother to Child Transmission,
PMTCT), pencegahan di kalangan pelanggan penjaja seks, dan lain-lain.
2. Perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP); yang meliputi penguatan dan
pengembangan layanan kesehatan, pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik,
pengobatan antiretroviral dan dukungan serta pendidikan dan pelatihan bagi ODHA.
Program PDP terutama ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan dan rawat inap,
angka kematian yang berhubungan dengan AIDS, dan meningkatkan kualitas hidup
orang terinfeksi HIV (berbagai stadium). Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan
antara lain dengan pemberian terapi antiretroviral (ARV).
3. Mitigasi dampak berupa dukungan psikososio-ekonomi.
4. Penciptaan lingkungan yang kondusif (creating enabling environment) yang meliputi
program peningkatan lingkungan yang kondusif adalah dengan penguatan
kelembagaan dan manajemen, manajemen program serta penyelarasan kebijakan dan
lain-lain.
KEGIATAN LAYANAN HIV DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN
Layanan terkait HIV meliputi upaya dalam menemukan pasien HIV secara dini dengan
melakukan tes dan konseling HIV pada pasien yang datang ke fasyankes, perawatan kronis
bagi Odha dan dukungan lain dengan sistem rujukan ke berbagai fasilitas layanan lain yang
dibutuhkan Odha.
Setiap daerah diharapkan menyediakan semua komponen layanan HIV yang terdiri dari :
1. Informed consent untuk tes HIV.
2. Mencatat semua kegiatan layanan dalam formulir yang sudah ditentukan
3. Anamnesis dan pemeriksaan fisik lengkap oleh dokter.
4. Skrining TB dan infeksi oportunistik
5. Konseling bagi Odha perempuan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi
termasuk rencana untuk mempunyai anak.
6. Pemberian obat kotrimoksasol sebagai pengobatan pencegahan infeksi oportunistik.
7. Pemberian ARV untuk Odha yang telah memenuhi syarat.
8. Pemberian ARV profilaksis pada bayi segera setelah dilahirkan oleh ibu hamil dengan
HIV.
9. Pemberian imunisasi dan pengobatan pencegahan kotrimoksasol pada bayi yang lahir
dari ibu dengan HIV positif.
10. Anjuran rutin tes HIV, malaria, sifilis dan IMS lainnya pada perawatan antenatal
(ANC).
11. Konseling untuk memulai terapi.
12. Konseling tentang gizi, pencegahan penularan, narkotika dan konseling lainnya sesuai
keperluan.
13. Menganjurkan tes HIV pada pasien TB, infeksi menular seksual (IMS), dan kelompok
risiko tinggi beserta pasangan seksualnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Pendampingan oleh lembaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien
KONSELING DAN TES HIV
Terdapat dua macam pendekatan untuk tes HIV
1) Konseling dan tes HIV sukarela (KTS-VCT = Voluntary Counseling & Testing)
2) Tes HIV dan konseling atas inisiatif petugas kesehatan (KTIP PITC = Provider-
Initiated Testing and Counseling)
KTIP merupakan kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan di layanan kesehatan yang
berarti semua petugas kesehatan harus menganjurkan tes HIV setidaknya pada ibu
hamil, pasien TB, pasien yang menunjukkan gejala dan tanda klinis diduga terinfeksi
HIV, pasien dari kelompok berisiko (penasun, PSK-pekerja seks komersial, LSL
lelaki seks dengan lelaki), pasien IMS dan seluruh pasangan seksualnya. Kegiatan
memberikan anjuran dan pemeriksaan tes HIV perlu disesuaikan dengan prinsip
bahwa pasien sudah mendapatkan informasi yang cukup dan menyetujui untuk tes
HIV dan semua pihak menjaga kerahasiaan (prinsip 3C counseling, consent,
confidentiality)
PEMERIKSAAN LABORATORIUM UNTUK TES HIV
Prosedur pemeriksaan laboratorium untuk HIV sesuai dengan panduan nasional yang berlaku
pada saat ini, yaitu dengan menggunakan strategi 3 dan selalu didahului dengan konseling pra
tes atau informasi singkat. Ketiga tes tersebut dapat menggunakan reagen tes cepat atau
dengan ELISA. Untuk pemeriksaan pertama (A1) harus digunakan tes dengan sensitifitas
yang tinggi (>99%), sedang untuk pemeriksaan selanjutnya (A2 dan A3) menggunakan tes
dengan spesifisitas tinggi (>99%).
Antibodi biasanya baru dapat terdeteksi dalam waktu 2 minggu hingga 3 bulan setelah
terinfeksi HIV yang disebut masa jendela. Bila tes HIV yang dilakukan dalam masa jendela
menunjukkan hasil negatif, maka perlu dilakukan tes ulang, terutama bila masih terdapat
perilaku yang berisiko.
Gambar 2. Bagan alur layanan HIV
PENEGAKAN DIAGNOSIS HIV
Setelah dinyatakan terinfeksi HIV maka pasien perlu dirujuk ke layanan PDP untuk
menjalankan serangkaian layanan yang meliputi penilaian stadium klinis, penilaian
imunologis dan penilaian virologi. Hal tersebut dilakukan untuk: 1) menentukan apakah
pasien sudah memenuhi syarat untuk terapi antiretroviral; 2) menilai status supresi imun
pasien; 3) menentukan infeksi oportunistik yang pernah dan sedang terjadi; dan 4)
menentukan paduan obat ARV yang sesuai.
A. Penilaian Stadium Klinis
Stadium klinis harus dinilai pada saat kunjungan awal dan setiap kali kunjungan untuk
penentuan terapi ARV dengan lebih tepat waktu.
B. Penilaian Imunologi (Pemeriksaan jumlah CD4)
Jumlah CD4 adalah cara untuk menilai status imunitas ODHA. Pemeriksaan CD4
melengkapi pemeriksaan klinis untuk menentukan pasien yang memerlukan
pengobatan profilaksis IO dan terapi ARV. Rata rata penurunan CD4 adalah sekitar
70-100 sel/mm3/tahun, dengan peningkatan setelah pemberian ARV antara 50 100
sel/mm3/tahun. Jumlah limfosit total (TLC) tidak dapat menggantikan pemeriksaan
CD4.
C. Pemeriksaan laboratorium sebelum memulai terapi
Pada dasarnya pemantauan laboratorium bukan merupakan persyaratan mutlak untuk
menginisiasi terapi ARV. Pemeriksaan CD4 dan viral load juga bukan kebutuhan
mutlak dalam pemantauan pasien yang mendapat terapi ARV, namun pemantauan
laboratorium atas indikasi gejala yang ada sangat dianjurkan untuk memantau
keamanan dan toksisitas pada ODHA yang menerima terapi ARV. Hanya apabila
sumberdaya memungkinkan maka dianjurkan melakukan pemeriksaan viral load pada
pasien tertentu untuk mengkonfirmasi adanya gagal terapi menurut kriteria klinis dan
imunologis.
Darah lengkap*
Jumlah CD4*
SGOT / SGPT*
Kreatinin Serum*
Urinalisa*
HbsAg*
Anti-HCV (untuk ODHA IDU atau dengan riwayat IDU)
Profil lipid serum
Gula darah
VDRL/TPHA/PRP
Ronsen dada (utamanya bila curiga ada infeksi paru)
Tes Kehamilan (perempuan usia reprodukstif dan perluanamnesis mens
terakhir)
PAP smear / IFA-IMS untuk menyingkirkan adanya Ca Cervix yang pada
ODHA bisa bersifat progresif)
Jumlah virus / Viral Load RNA HIV** dalam plasma (bila tersedia dan bila
pasien mampu)
Catatan:
* adalah pemeriksaan yang minimal perlu dilakukan sebelum terapi ARV karena
berkaitan dengan pemilihan obat ARV. Tentu saja hal ini perlu mengingat
ketersediaan sarana dan indikasi lainnya.
** pemeriksaan jumlah virus memang bukan merupakan anjuran untuk dilakukan
sebagai pemeriksaan awal tetapi akan sangat berguna (bila pasien punya data)
utamanya untuk memantau perkembangan dan menentukan suatu keadaan gagal
terapi.
D. Persyaratan lain sebelum memulai terapi ARV
Sebelum mendapat terapi ARV pasien harus dipersiapkan secara matang dengan
konseling kepatuhan karena terapi ARV akan berlangsung seumur hidupnya.
Untuk ODHA yang akan memulai terapi ARV dalam keadaan jumlah CD4 di bawah
200 sel/mm3 maka dianjurkan untuk memberikan Kotrimoksasol (1x960mg sebagai
pencegahan IO) 2 minggu sebelum terapi ARV. Hal ini dimaksudkan untuk: 1.
Mengkaji kepatuhan pasien untuk minum obat,dan 2. Menyingkirkan kemungkinan
efek samping tumpang tindih antara kotrimoksasol dan obat ARV, mengingat bahwa
banyak obat ARV mempunyai efek samping yang sama dengan efek samping
kotrimoksasol.
TATALAKSANA PEMBERIAN ARV
A. Saat Memulai Terapi ARV
Untuk memulai terapi antiretroviral perlu dilakukan pemeriksaan jumlah CD4 (bila tersedia)
dan penentuan stadium klinis infeksi HIV-nya. Hal tersebut adalah untuk menentukan apakah
penderita sudah memenuhi syarat terapi antiretroviral atau belum. Berikut ini adalah
rekomendasi cara memulai terapi ARV pada ODHA dewasa.
a. Tidak tersedia pemeriksaan CD4
Dalam hal tidak tersedia pemeriksaan CD4, maka penentuan mulai terapi ARV adalah
didasarkan pada penilaian klinis.
b. Tersedia pemeriksaan CD4
Rekomendasi :
1. Mulai terapi ARV pada semua pasien dengan jumlah CD4 <350 sel/mm3
tanpa memandang stadium klinisnya.
2. Terapi ARV dianjurkan pada semua pasien dengan TB aktif, ibu hamil dan
koinfeksi Hepatitis B tanpa memandang jumlah CD4.
Tabel 6. Saat memulai terapi pada ODHA dewasa
Paduan ARV Lini Pertama yang Dianjurkan
Pemerintah menetapkan paduan yang digunakan dalam pengobatan ARV berdasarkan pada 5
aspek yaitu:
Efektivitas
Efek samping / toksisitas
Interaksi obat
Kepatuhan
Harga obat
Prinsip dalam pemberian ARV adalah
1. Paduan obat ARV harus menggunakan 3 jenis obat yang terserap dan berada dalam
dosis terapeutik. Prinsip tersebut untuk menjamin efektivitas penggunaan obat.
2. Membantu pasien agar patuh minum obat antara lain dengan mendekatkan akses
pelayanan ARV .
3. Menjaga kesinambungan ketersediaan obat ARV dengan menerapkan manajemen
logistik yang baik.
ANJURAN PEMILIHAN OBAT ARV LINI PERTAMA
Paduan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk lini pertama adalah: 2 NRTI + 1 NNRTI
1. Memulai dan Menghentikan Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor
(NNRTI)
Nevirapine dimulai dengan dosis awal 200 mg setiap 24 jam selama 14 hari pertama
dalam paduan ARV lini pertama bersama AZT atau TDF + 3TC. Bila tidak ditemukan
tanda toksisitas hati, dosis dinaikkan menjadi 200 mg setiap 12 jam pada hari ke-15
dan selanjutnya. Mengawali terapi dengan dosis rendah tersebut diperlukan karena
selama 2 minggu pertama terapi NVP menginduksi metabolismenya sendiri. Dosis
awal tersebut juga mengurangi risiko terjadinya ruam dan hepatitis oleh karena NVP
yang muncul dini.
Bila NVP perlu dimulai lagi setelah pengobatan dihentikan selama lebih dari 14 hari,
maka diperlukan kembali pemberian dosis awal yang rendah tersebut.
Cara menghentikan paduan yang mengandung NNRTI
Hentikan NVP atau EFV
Teruskan NRTI (2 obat ARV saja) selama 7 hari setelah penghentian Nevirapine
dan Efavirenz, (ada yang menggunakan 14 hari setelah penghentian Efavirenz)
kemudian hentikan semua obat. Hal tersebut guna mengisi waktu paruh NNRTI
yang panjang dan menurunkan risiko resistensi NNRTI.
Penggunaan NVP dan EFV
NVP dan EFV mempunyai efikasi klinis yang setara
Ada perbedaan dalam profil toksisitas, potensi interaksi dengan obat lain, dan
harga
NVP berhubungan dengan insidensi ruam kulit, sindrom Steven-Johnson dan
hepatotoksisitas yang lebih tinggi dibanding EFV.
Dalam keadaan reaksi hepar atau kulit yang berat maka NVP harus dihentikan dan
tidak boleh dimulai lagi
Gunakan NVP atau PI untuk ibu hamil trimester 1 atau triple NRTI jika NVP dan
PI tidak dapat digunakan. Triple NRTI hanya diberikan selama 3 bulan lalu
dikembalikan kepada paduan lini pertama
Perlu kehati-hatian penggunaan NVP pada perempuan dengan CD4 >250 sel/mm3
atau yang tidak diketahui jumlah CD4-nya dan pada laki-laki dengan jumlah CD4
>400 sel/mm3 atau yang tidak diketahui jumlah CD4-nya.
Perlu dilakukan lead-in dosing pada penggunaan NVP, yaitu diberikan satu kali
sehari selama 14 hari pertama kemudian dilanjutkan dengan 2 kali sehari.
EFV dapat digunakan sekali sehari dan biasanya ditoleransi dengan baik, hanya
saja biayanya lebih mahal dan kurang banyak tersedia dibandingkan NVP
Toksisitas utama EFV adalah berhubungan dengan sistem saraf pusat (SSP) dan
ada kemungkinan (meski belum terbukti kuat) bersifat teratogenik bila diberikan
pada trimester 1 (tetapi tidak pada triemester dua dan tiga) dan ruam kulit yang
biasanya ringan dan hilang sendiri tanpa harus menghentikan obat. Gejala SSP
cukup sering terjadi, dan meskipun biasanya hilang sendiri dalam 2-4 minggu,
gejala tersebut dapat bertahan beberapa bulan dan sering menyebabkan
penghentian obat oleh pasien
EFV perlu dihindari pada pasien dengan riwayat penyakit psikiatrik berat, pada
perempuan yang berpotensi hamil dan pada kehamilan trimester pertama.
EFV merupakan NNRTI pilihan pada keadaan ko-infeksi TB/HIV yang mendapat
terapi berbasis Rifampisin. Dalam keadaan penggantian sementara dari NVP ke
EFV selama terapi TB dengan Rifampisin dan akan mengembalikan ke NVP
setelah selesai terapi TB maka tidak perlu dilakukan lead-in dosing.
2. Pilihan pemberian Triple NRTI
Regimen triple NRTI digunakan hanya jika pasien tidak dapat menggunakan obat
ARV berbasis NNRTI, seperti dalam keadaan berikut:
Ko-infeksi TB/HIV, terkait dengan interaksi terhadap Rifampisin
Ibu Hamil, terkait dengan kehamilan dan ko-infeksi TB/HIV
Hepatitis, terkait dengan efek hepatotoksik karena NVP/EFV/PI
Anjuran paduan triple NRTI yang dapat dipertimbangkan adalah AZT+3TC +TDF
Penggunaan Triple NRTI dibatasi hanya untuk 3 bulan lamanya, setelah itu pasien
perlu di kembalikan pada penggunaan lini pertama karena supresi virologisnya kurang
kuat.
3. Penggunaan AZT dan TDF
AZT dapat menyebabkan anemi dan intoleransi gastrointestinal
Indeks Massa Tubuh (IMT / BMI = Body Mass Index) dan jumlah CD4 yang
rendah merupakan faktor prediksi terjadinya anemi oleh penggunaan AZT
Perlu diketahui faktor lain yang berhubungan dengan anemi, yaitu antara lain
malaria, kehamilan, malnutrisi dan stadium HIV yang lanjut
TDF dapat menyebabkan toksisitas ginjal. Insidensi nefrotoksisitas dilaporkan
antara 1% sampai 4% dan angka Sindroma Fanconi sebesar 0.5% sampai 2%
TDF tidak boleh digunakan pada anak dan dewasa muda dan sedikit data tentang
keamanannya pada kehamilan
TDF juga tersedia dalam sediaan FDC (TDF+FTC) dengan pemberian satu kali
sehari yang lebih mudah diterima ODHA
4. Perihal Penggunaan d4T
Stavudin (d4T) merupakan ARV dari golongan NRTI yang poten dan telah
digunakan terutama oleh negara yang sedang berkembang dalam kurun waktu
yang cukup lama. Keuntungan dari d4T adalah tidak membutuhkan data
laboratorium awal untuk memulai serta harganya yang relatif sangat terjangkau
dibandingkan dengan NRTI yang lain seperti Zidovudin (terapi ARV), Tenofovir
(TDF) maupun Abacavir (ABC). Namun dari hasil studi didapat data bahwa
penggunaan d4T, mempunyai efek samping permanen yang bermakna, antara lain
lipodistrofi dan neuropati perifer yang menyebabkan cacat serta laktat asidosis
yang menyebabkan kematian.
Efek samping karena penggunaan d4T sangat berkorelasi dengan lama
penggunaan d4T (semakin lama d4T digunakan semakin besar kemungkinan
timbulnya efek samping). WHO dalam pedoman tahun 2006 merekomendasikan
untuk mengevaluasi penggunaan d4T setelah 2 tahun dan dalam pedoman
pengobatan ARV untuk dewasa tahun 2010 merekomendasikan untuk secara
bertahap mengganti penggunaan d4T dengan Tenofovir (TDF).
Berdasarkan kesepakatan dengan panel ahli, maka pemerintah memutuskan
sebagai berikut:
o Menggunakan AZT atau TDF pada pasien yang baru memulai terapi dan
belum pernah mendapat terapi ARV sebelumnya
o Pada pasien yang sejak awal menggunakan d4T dan tidak dijumpai efek
samping dan/atau toksisitas maka direkomendasikan untuk diganti setelah
6 bulan
o Jika terjadi efek samping akibat penggunaan AZT (anemia), maka sebagai
obat substitusi gunakan TDF.
o Pada saat sekarang penggunaan Stavudin (d4T) dianjurkan untuk dikurangi
karena banyaknya efek samping. Secara nasional dilakukan penarikan
secara bertahap (phasing out) dan mendatang tidak menyediakan lagi d4T
setelah stok nasional habis.
5. Penggunaan Protease Inhibitor (PI)
Obat ARV golongan Protease Inhibitor (PI) TIDAK dianjurkan untuk terapi Lini
Pertama, hanya digunakan sebagai Lini Kedua. Penggunaan pada Lini Pertama hanya
bila pasien benar-benar mengalami Intoleransi terhadap golongan NNRTI (Efavirenz
atau Nevirapine). Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghilangkan kesempatan
pilihan untuk Lini Kedua. mengingat sumber daya yang masih terbatas
SINDROM PULIH IMUN (SPI - IMMUNE RECONSTITUTION SYNDROME = IRIS)
Sindrom Pulih Imun (SPI) atau Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS)
adalah perburukan kondisi klinis sebagai akibat respons inflamasi berlebihan pada saat
pemulihan respons imun setelah pemberian terapi antiretroviral. Sindrom pulih imun
mempunyai manifestasi dalam bentuk penyakit infeksi maupun non infeksi. Manifestasi
tersering pada umumnya adalah berupa inflamasi dari penyakit infeksi. Sindrom pulih imun
infeksi ini didefinisikan sebagai timbulnya manifestasi klinis atau perburukan infeksi yang
ada sebagai akibat perbaikan respons imun spesifik patogen pada ODHA yang berespons baik
terhadap ARV.
Mekanisme SPI belum diketahui dengan jelas, diperkirakan hal ini merupakan respon imun
berlebihan dari pulihnya sistem imun terhadap rangsangan antigen tertentu setelah pemberian
ARV.
Insidens sindrom pulih imun secara keseluruhan berdasarkan meta analisis adalah 16.1%.
Namun, insidens ini juga berbeda pada tiap tempat, tergantung pada rendahnya derajat sistem
imun dan prevalensi infeksi oportunistik dan koinfeksi dengan patogen lain.
Pada saat ini dikenal dua jenis SPI yang sering tumpang tindih, yaitu sindrom pulih imun
unmasking (unmasking IRD) dan sindrom pulih imun paradoksikal. Jenis unmasking terjadi
pada pasien yang tidak terdiagnosis dan tidak mendapat terapi untuk infeksi oportunistiknya
dan langsung mendapatkan terapi ARV-nya. Pada jenis paradoksikal, pasien telah
mendapatkan pengobatan untuk infeksi oportunistiknya. Setelah mendapatkan ARV, terjadi
perburukan klinis dari penyakit infeksinya tersebut.
Manifestasi klinis yang muncul sangat bervariasi dan tergantung dari bahan infeksi atau non-
infeksi yang terlibat, sehingga diagnosis menjadi tidak mudah. Pada waktu menegakkan
diagnosis SPI perlu dicantumkan penyakit infeksi atau non infeksi yang menjadi
penyebabnya (misal IRIS TB, IRIS Toxoplasmosis).
International Network Study of HIV-associated IRIS (INSHI) membuat konsensus untuk
kriteria diagnosis sindrom pulih imun sebagai berikut.
Menunjukkan respons terhadap terapi ARV dengan:
1. mendapat terapi ARV
2. penurunan viral load > 1 log kopi/ml (jika tersedia)
Perburukan gejala klinis infeksi atau timbul reaksi inflamasi yang terkait dengan
inisiasi terapi ARV
Gejala klinis tersebut bukan disebabkan oleh:
1. Gejala klinis dari infeksi yang diketahui sebelumnya yang telah berhasil
disembuhkan (Expected clinical course of a previously recognized and
successfully treated infection)
2. Efek samping obat atau toksisitas
3. Kegagalan terapi
4. Ketidakpatuhan menggunakan ARV
Beberapa faktor risiko terjadinya SPI adalah jumlah CD4 yang rendah saat memulai terapi
ARV, jumlah virus RNA HIV yang tinggi saat memulai terapi ARV, banyak dan beratnya
infeksi oportunistik, penurunan jumlah virus RNA HIV yang cepat selama terapi ARV,
belum pernah mendapat ARV saat diagnosis infeksi oportunistik, dan pendeknya jarak waktu
antara memulai terapi infeksi oportunistik dan memulai terapi ARV.
Tatalaksana SPI meliputi pengobatan patogen penyebab untuk menurunkan jumlah antigen
dan meneruskan terapi ARV. Terapi antiinflamasi seperti obat antiiflamasi non steroid dan
steroid dapat diberikan. Dosis dan lamanya pemberian kortikosteroid belum pasti, berkisar
antara 0,5- 1 mg/kg/hari prednisolon.
TERAPI ANTIRETROVIRAL PADA POPULASI KHUSUS
Terdapat beberapa kelompok dan keadaan khusus yang memerlukan suatu perhatian khusus
ketika akan memulai terapi antiretroviral. Kelompok khusus tersebut antara lain kelompok
perempuan hamil; kelompok pecandu NAPZA suntik dan yang menggunakan Metadon.
Sementara keadaan khusus yang perlu diperhatikan adalah keadaan Koinfeksi HIV dengan
TB dan Koinfeksi HIV dengan Hepatitis B dan C.
Terapi ARV untuk ibu hamil
o Terapi antiretroviral/ARV/HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy)
dalam program PMTCT (Prevention Mother to Child Transmission PPIA =
Pencegahan Penularan Ibu ke Anak) adalah penggunaan obat antiretroviral
jangka panjang (seumur hidup) untuk mengobati perempuan hamil HIV positif
dan mencegah penularan HIV dari ibu ke anak.
o Pemberian obat antiretroviral dalam program PMTCT/PPIA ditujukan pada
keadaan seperti terpapar berikut ini.
Terapi ARV untuk Ko-infeksi HIV/Hepatitis B (HBV) dan Hepatitis C (HCV)
Hepatitis merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui darah (blood borne
disease) dan merupakan salah satu penyakit ko-infeksi pada HIV khususnya hepatitis
B & C. Infeksi hepatitis C sering dijumpai sebagai ko-infeksi pada ODHA pengguna
NAPZA suntik. Infeksi hepatitis B dan hepatitis C tidak mempengaruhi progresivitas
penyakit HIV, namun infeksi HIV akan mempercepat progresivitas penyakit hepatitis
B dan C dan mempercepat terjadinya end stage liver disease (ESLD)
Terapi ARV untuk koinfeksi hepatitis B
o Hepatitis B dan HIV mempunyai beberapa kemiripan karakter, di antaranya
adalah merupakan blood-borne disease, membutuhkan pengobatan seumur
hidup, mudah terjadi resisten terutama jika digunakan monoterapi dan
menggunakan obat yang sama yaitu Tenofovir, lamivudine dan emtricitabine.
Entecavir, obat anti hepatits B mempunyai efek anti retroviral pada HIV juga
akan tetapi tidak digunakan dalam pengobatan HIV.
o Perlu diwaspadai timbulnya flare pada pasien ko-infeksi HIV/Hep B jika
pengobatan HIV yang menggunakan TDF/3TC dihentikan karena alasan
apapun.
o Mulai ART pada semua individu dengan ko-infeksi HIV/HBV yang
memerlukan terapi untuk infeksi HBV-nya (hepatitis kronik aktif), tanpa
memandang jumlah CD4 atau stadium klinisnya. Perhimpunan Peneliti Hati
Indonesia (PPHI) merekomendasikan memulai terapi hepatitis B pada infeksi
hepatitis B kronik aktif jika terdapat: peningkatan SGOT/SGPT lebih dari 2
kali selama 6 bulan dengan HBeAg positif atau HBV DNA positif.
o Adanya rekomendasi tersebut mendorong untuk dilakukan diagnosis HBV
pada HIV dan terapi yang efektif untuk ko-infeksi HIV/HBV
o Gunakan paduan antiretroviral yang mengandung aktivitas terhadap HBV dan
HIV, yaitu TDF + 3TC atau FTC untuk peningkatan respon VL HBV dan
penurunan perkembangan HBV yang resistensi obat
o Pada pengobatan ARV untuk koinfeksi hepatitis B perlu diwaspadai
munculnya hepatic flare dari hepatitis B. Penampilan flare khas sebagai
kenaikan tidak terduga dari SGPT/SGOT dan munculnya gejala klinis
hepatitis (lemah, mual, nyeri abdomen, dan ikterus) dalam 6-12 minggu
pemberian ART. Flares sulit dibedakan dari reaksi toksik pada hati yang
dipicu oleh ARV atau obat hepatotoksik lainnya seperti kotrimoksasol, OAT,
atau sindrom pulih imun hepatitis B. Obat anti Hepatitis B harus diteruskan
selama gejala klinis yang diduga flares terjadi. Bila tidak dapat membedakan
antara kekambuhan hepatitis B yang berat dengan gejala toksisitas ARV
derajat 4, maka terapi ARV perlu dihentikan hingga pasien dapat distabilkan.
Penghentian TDF, 3TC, atau FTC juga dapat menyebabkan hepatic flare.
Terapi ARV untuk koinfeksi hepatitis C
o Zidovudine dan Stavudine mempunyai efek samping tumpang tindih dalam
hal hematologi dan hepatotoksisitas dengan pengobatan yang digunakan dalam
hepatitis C khususnya ribavirin seperti pada tabel 12. Oleh karena itu, pada
saat pemberian bersama terapi hepatitis C perlu dilakukan substitusi sementara
dengan TDF.
o Terapi hepatitis C dianjurkan dimulai pada saat CD4 > 350 sel/mm3 dan
setelah terapi ARV stabil untuk mencapai tingkat SVR yang lebih tinggi.
TERAPI ARV UNTUK PROFILAKSIS PASCA PAJANAN (PPP ATAU POST
EXPOSURE PROPHYLAXIS = PEP)
Terapi antiretroviral (ARV) dapat pula digunakan untuk Pencegahan Pasca Pajanan (PPP atau
PEP = post exposure prophylaxis), terutama untuk kasus pajanan di tempat kerja
(Occupational exposure). Risiko penularan HIV melalu tusukan jarum suntik adalah kurang
dari 1%. PPP dapat juga dipergunakan dalam beberapa kasus seksual yang khusus misal
perkosaan atau keadaan pecah kondom pada pasangan suami istri.
Beberapa hal tentang PPP:
Waktu yang terbaik adalah diberikan sebelum 4 jam dan maksimal dalam 48-72 jam
setelah kejadian
Paduan yang dianjurkan adalah AZT + 3TC + EFV atau AZT + 3TC + LPV/r
(Lopinavir/Ritonavir)
Nevirapine (NVP) TIDAK digunakan untuk PPP
ARV untuk PEP diberikan selama 1 bulan
Perlu dilakukan tes HIV sebelum memulai PPP
ARV TIDAK diberikan untuk tujuan PPP jika tes HIV menunjukkan hasil reaktif
(karena berarti yang terpajan sudah HIV positif sebelum kejadian)
Perlu dilakukan pemantauan efek samping dari obat ARV yang diminum
Perlu dilakukan Tes HIV pada bulan ke 3 dan 6 setelah pemberian PPP
Pada kasus kecelakaan kerja pada petugas yang menderita Hepatitis B maka PPP yang
digunakan sebaiknya mengandung TDF/3TC untuk mencegah terjadinya hepatic
flare.
PEMANTAUAN KLINIS DAN LABORATORIS SELAMA TERAPI ARV LINI
PERTAMA
Pemantauan pasien dengan infeksi HIV dilakukan baik pada pasien yang belum memenuhi
syarat terapi antiretroviral dan terlebih pada pasien yang sudah memulai terapinya.
Enam bulan sejak memulai terapi ARV merupakan masa yang kritis dan penting. Diharapkan
dalam masa tersebut akan terjadi perkembangan klinis dan imunologis ke arah yang lebih
baik, meskipun hal tersebut kadang tidak terjadi dan atau terjadi toksisitas obat.
Berbagai faktor mempengaruhi perbaikan klinis maupun imunologis sejak memulai ART,
antara lain beratnya keadaan klinis dan rendahnya jumlah CD4 saat memulai. Selain itu perlu
diingat juga bahwa pemulihan keadaan klinis dan imunologis tersebut memerlukan waktu
untuk bisa terjadi dan menunjukkan hasil. Di bawah akan diulas beberapa hal yang perlu
dipantau pada pasien yang belum maupun sudah mulai mendapat terapi ARV, baik pada 6
bulan pertama maupun pemantauan jangka panjang.
A. Pasien yang belum memenuhi syarat terapi ARV
Pasien yang belum memenuhi syarat terapi antiretroviral (terapi ARV) perlu dimonitor
perjalanan klinis penyakit dan jumlah CD4-nya setiap 6 bulan sekali. Evaluasi klinis meliputi
parameter seperti pada evaluasi awal termasuk pemantauan berat badan dan munculnya tanda
dan gejala klinis perkembangan infeksi HIV.
Parameter klinis dan jumlah CD4 tersebut digunakan untuk mencatat perkembangan stadium
klinis pada setiap kunjungan dan menentukan saat pasien mulai memenuhi syarat untuk terapi
profilaksis kotrimoksazol dan atau terapi ARV. Berbagai faktor mempengaruhi
perkembangan klinis dan imunologis sejak terdiagnosis terinfeksi HIV. Penurunan jumlah
CD4 setiap tahunnya adalah sekitar 50 sampai 100 sel/mm3. Evaluasi klinis dan jumlah CD4
perlu dilakukan lebih ketat ketika mulai mendekati ambang dan syarat untuk memulai terapi
ARV.
B. Pemantauan Pasien dalam Terapi Antiretroviral
1. Pemantauan klinis
Frekuensi Pemantauan klinis tergantung dari respon terapi ARV. Sebagai batasan minimal,
Pemantauan klinis perlu dilakukan pada minggu 2, 4, 8, 12 dan 24 minggu sejak memulai
terapi ARV dan kemudian setiap 6 bulan bila pasien telah mencapai keadaan stabil.
Pada setiap kunjungan perlu dilakukan penilaian klinis termasuk tanda dan gejala efek
samping obat atau gagal terapi dan frekuensi infeksi (infeksi bakterial, kandidiasis dan atau
infeksi oportunirtik lainnya) ditambah konseling untuk membantu pasien memahami terapi
ARV dan dukungan kepatuhan.
2. Pemantauan laboratoris
lebih sering bila ada indikasi klinis. Angka limfosit total (TLC = total lymphocyte count)
tidak direkomendasikan untuk digunakan memantau terapi karena perubahan nilai TLC tidak
dapat digunakan untuk memprediksi keberhasilan terapi
kadar Hemoglobin (Hb) sebelum memulai terapi dan pada minggu ke 4, 8 dan 12 sejak mulai
terapi atau ada indikasi tanda dan gejala anemia
gejala dan bukan berdasarkan sesuatu yang rutin. Akan tetapi bila menggunakan NVP untuk
perempuan dengan CD4 antara 250 350 sel/mm3 maka perlu dilakuan pemantauan enzim
transaminase pada minggu 2, 4, 8 dan 12 sejak memulai terapi ARV (bila memungkinkan),
dilanjutkan dengan pemantauan berdasar gejala klinis
l perlu dilakukan untuk pasien yang mendapatkan TDF
mendapatkan NRTI, terutama d4T atau ddI. Tidak direkomendasi untuk pemeriksaan kadar
asam laktat secara rutin, kecuali bila pasien menunjukkan tanda dan gejala yang mengarah
pada asidosis laktat
Beberapa ahli menganjurkan pemeriksaan gula darah dan profil lipid secara reguler tetapi
lebih diutamakan untuk dilakukan atas dasar tanda dan gejala
Viral Load (VL) sampai sekarang tidak dianjurkan untuk memantau pasien
dalam terapi ARV dalam keadaan terbatas fasilitas dan kemampuan pasien. Pemeriksaan VL
digunakan untuk membantu diagnosis gagal terapi. Hasil VL
dapat memprediksi gagal terapi lebih awal dibandingkan dengan hanya menggunakan
pemantauan klinis dan pemeriksaan jumlah CD4
menjadi tidak terdeteksi (undetectable) setelah bulan ke 6.
3. Pemantauan pemulihan jumlah sel CD4
Pemberian terapi ARV akan meningkatkan jumlah CD4. Hal ini akan berlanjut bertahun-
tahun dengan terapi yang efektif. Keadaan tersebut, kadang tidak terjadi, terutama pada
pasien dengan jumlah CD4 yang sangat rendah pada saat mulai terapi. Meskipun demikian,
pasien dengan jumlah CD4 yang sangat rendah tetap dapat mencapai pemulihan imun yang
baik tetapi memerlukan waktu yang lebih lama.
Pada pasien yang tidak pernah mencapai jumlah CD4 yang lebih dari 100 sel/mm3 dan atau
pasien yang pernah mencapai jumlah CD4 yang tinggi tetapi kemudian turun secara progresif
tanpa ada penyakit/kondisi medis lain, maka perlu dicurigai adanya keadaan gagal terapi
secara imunologis.
Data jumlah CD4 saat mulai terapi ARV dan perkembangan CD4 yang dievaluasi tiap 6
bulan sangat diperlukan untuk menentukan adanya gagal terapi secara imunologis. Pada
sebagian kecil pasien dengan stadium lanjut dan jumlah CD4 yang rendah pada saat mulai
terapi ARV, kadang jumlah CD4 tidak meningkat atau sedikit turun meski terjadi perbaikan
klinis.
4. Kematian dalam Terapi Antriretroviral
Sejak dimulainya terapi ARV, angka kematian yang berhubungan dengan HIV semakin
turun. Secara umum, penyebab kematian pasien dengan infeksi HIV disebabkan karena
penanganan infeksi oportunistik yang tidak adekuat, efek samping ARV berat (Steven
Johnson Syndrome), dan keadaan gagal fungsi hati stadium akhir (ESLD - End Stage Liver
Disease) pada kasus ko-infeksi HIV/HVB.
Paradigma baru yang menjadi tujuan global dari UNAIDS adalah Zero AIDS-related death.
Hal ini dapat tercapai bila pasien datang di layanan HIV dan mendapat terapi ARV
secepatnya.
Keterangan:
[a] Hasil tes HIV (+) yang tercatat (meskipun sudah lama) sudah cukup untuk dasar memulai
terapi ARV. Bila tidak ada dokumen tertulis, dianjurkan untuk dilakukan tes HIV sebelum
memulai terapi ARV
[b] Bagi pasien yang mendapat AZT: perlu di periksa kadar hemoglobin sebelum terapi AZT
dan pada minggu ke 4, 8 dan 12, dan bila diperlukan (misal ada tanda dan gejala anemia atau
adanya obat lain yang bisa menyebabkan anemia).
[c] Lakukan tes kehamilan sebelum memberikan EFV pada ODHA perempuan usia subur.
Bila hasil tes positif dan kehamilan pada trimester pertama maka jangan diberi EFV.
[d] Bila hasil tes kehamilan positif pada perempuan yang sudah terlanjur mendapatkan EFV
maka segera ganti dengan paduan yang tidak mengandung EFV
[e] Pasien yang mendapat TDF, perlu pemeriksaan kreatinin serum pada awal, dan setiap 3
bulan pada tahun pertama kemudian jika stabil dapat dilakukan setiap 6 bulan.
[f] Pengukuran viral load (HIV RNA) tidak dianjurkan sebagai dasar pengambilan keputusan
untuk memulai terapi ARV atau sebagai alat pemantau respon pengobatan pada saat tersebut.
Dapat dipertimbangkan sebagai diagnosis dini adanya kegagalan terapi atau menilai adanya
ketidaksesuaian antara hasil CD4 dan keadaan klinis dari pasien yang diduga mengalami
kegagalan terapi ARV.
EFEK SAMPING
8 KEGAGALAN TERAPI ARV
Apabila setelah memulai terapi minimal 6 bulan dengan kepatuhan yang tinggi tetapi tidak
terjadi respon terapi yang kita harapkan, maka perlu dicurigai kemungkinan terjadinya Gagal
Terapi.
Kriteria gagal terapi adalah menggunakan 3 kriteria, yaitu kriteria klinis, imunologis dan
virologis. Jumlah virus (VL) yang menetap di atas 5000 copies/ml mengkonfirmasi gagal
terapi. Bila pemeriksaan VL tidak tersedia, untuk menentukan gagal terapi menggunakan
kriteria imunologis untuk memastikan gagal terapi secara klinis.
A. Definisi
Kriteria gagal terapi, ditentukan berdasarkan kriteria klinis, imunologis maupun virologis.
Pada tempat dimana tidak tersedia sarana pemeriksaan CD4 dan atau viral load, maka
diagnosa kegagalan terapi menurut gejala klinis dapat dilakukan. Sebaliknya pada tempat
yang mempunyai sarana pemeriksaan CD4 dan atau viral load, maka diagnosa kegagalan
terapi ditegakkan dengan panduan pemeriksaan CD4 dan atau viral load setelah pada
pemeriksaan fisik dijumpai tampilan gejala klinis yang mengarah pada kegagalan terapi. Di
bawah akan diulas dua macam kriteri kegagalan terapi, yang pertama adalah yang
menggunakan pemeriksaan CD4 dan VL sebagai dasar penentuan (kriteria WHO) dan yang
menggunakan pemeriksaan klinis sebagai dasar penentuan gagal terapi (utamanya digunakan
pada tempat yang tidak memiliki sarana pemerikasaan CD4 dan VL).
Kegagalan terapi menurut kriteria WHO
1. Kegagalan klinis:
Munculnya IO dari kelompok stadium 4 setelah minimal 6 bulan dalam terapi ARV.
Beberapa penyakit yang termasuk dalam stadium klinis 3 (TB paru, infeksi bakteri berat)
dapat merupakan petunjuk kegagalan terapi.
2. Kegagalan Imunologis
Definisi dari kegagalan imunologis adalah gagal mencapai dan mempertahankan jumlah CD4
yang adekuat, walaupun telah terjadi penurunan/ penekanan jumlah virus.
Pola 1 : CD4 < 100 / mm
Pola 2 : Setelah satu tahun terapi CD4 kembali atau lebih rendah daripada awal terapi ARV
Pola 3 : CD4 sebesar 50% dari nilai tertinggi yang pernah dicapai selama terapi terapi ARV
(bila diketahui)
Jumlah CD4 juga dapat digunakan untuk menentukan apakah perlu mengubah terapi atau
tidak. Sebagai contoh, munculnya penyakit baru yang termasuk dalam stadium 3, dimana
dipertimbangkan untuk mengubah terapi, maka bila jumlah CD4 >200 /mm tidak dianjurkan
untuk mengubah terapi.
3. Kegagalan Virologis:
Disebut gagal virologis jika:
viral load tetap > 5.000 copies/ml (lihat gambar.4), atau
viral load menjadi terdeteksi lagi setelah sebelumnya tidak terdeteksi.
Kriteria klinis untuk gagal terapi yang timbul dalam 6 bulan pertama pengobatan tidak dapat
dijadikan dasar untuk mengatakan gagal terapi. Perlu dilihat kemungkinan penyebab lain
timbulnya keadaan klinis tersebut, misal IRIS.
Kriteria virologi dimasukkan dalam menentukan kegagalan terapi di buku ini, untuk
mengantisipasi suatu saat akan tersedia sarana pemeriksaan viral load yang terjangkau. Viral
load masih merupakan indikator yang paling sensitif dalam menentukan adanya kegagalan
terapi. Kadar viral load yang optimal sebagai batasan untuk mengubah paduan ARV belum
dapat ditentukan dengan pasti. Namun > 5.000 copies/ml diketahui berhubungan dengan
progresi klinis yang nyata atau turunnya jumlah CD4.
B. Alur Tatalaksana Gagal Terapi ARV kriteria WHO
Berikut adalah alur tatalaksana bila dicurigai terjadi gagal terapi.
Definisi dan kriteria gagal terapi menurut gejala klinis yang lain adalah timbulnya keadaan
PPE atau Prurigo, kedua gejala bisa menjadi dasar untuk kecurigaan terjadinya gagal terapi.
Kriteria ini lebih untuk keadaan dimana tidak tersedia fasilitas pemeriksaan CD4 dan atau
Viral Load. (lihat Gambar 5). Indonesia dapat menggunakan kriteria ini dengan dasar
pemikiran belum semua tempat memiliki sarana pemeriksaan CD4 atau viral load.
Gambar 5. Alur Tatalaksana Gagal Terapi Menurut Kriteria Klinis
Pada kasus gagal terapi tindakan yang direkomendasikan adalah mengganti (switch) paduan
lini-pertama menjadi paduan lini-kedua.
C. Paduan Terapi Antiretroviral Lini Kedua
2 NRTI + boosted-PI
(boost) dengan Ritonavir sehingga
obat tersebut akan ditulis dengan kode ..../r (misal LPV/r = Lopinavir/ritonavir)
booster) dengan ritonavir ini dimaksudkan untuk mengurangi dosis dari obat
PI-nya karena kalau tanpa ritonavir maka dosis yang diperlukan menjadi tinggi sekali.
adalah: TDF atau AZT + 3TC + LPV/r
FTC) sebagai dasar NRTI pada paduan lini kedua
NRTI sebagai dasar NRTI pada paduan lini kedua
Anda mungkin juga menyukai
- Presentasi Campak - EllenDokumen14 halamanPresentasi Campak - EllenellenjapBelum ada peringkat
- OLIGODENDROGLIOMADokumen32 halamanOLIGODENDROGLIOMAellenjapBelum ada peringkat
- Referat SCTDokumen48 halamanReferat SCTellenjapBelum ada peringkat
- ASI Perah LeafletDokumen2 halamanASI Perah LeafletellenjapBelum ada peringkat
- Weil's DiseaseDokumen22 halamanWeil's DiseaseellenjapBelum ada peringkat
- MikrokolonDokumen18 halamanMikrokolonellenjapBelum ada peringkat
- AsfiksiaDokumen55 halamanAsfiksiaellenjapBelum ada peringkat
- SKDIDokumen42 halamanSKDIellenjapBelum ada peringkat
- Penyakit THT Yang Berhubungan Dengan MataDokumen39 halamanPenyakit THT Yang Berhubungan Dengan MataellenjapBelum ada peringkat
- Komplikasi SinusitisDokumen20 halamanKomplikasi SinusitisFerdy MorezaBelum ada peringkat
- Patient Safety (OHSAS Dan OSHA)Dokumen4 halamanPatient Safety (OHSAS Dan OSHA)Fongmeicha Elizabeth MargarethaBelum ada peringkat
- SKDIDokumen42 halamanSKDIellenjapBelum ada peringkat
- AsfiksiaDokumen55 halamanAsfiksiaellenjapBelum ada peringkat
- Penyakit THT Yang Berhubungan Dengan MataDokumen39 halamanPenyakit THT Yang Berhubungan Dengan MataellenjapBelum ada peringkat
- KandidosisDokumen16 halamanKandidosisellenjapBelum ada peringkat
- Dislipidemia & HipertensiDokumen9 halamanDislipidemia & HipertensiellenjapBelum ada peringkat
- Gigitan ScolopendraDokumen5 halamanGigitan ScolopendraellenjapBelum ada peringkat
- OzaenaDokumen10 halamanOzaenaellenjapBelum ada peringkat
- Herpes SimpleksDokumen4 halamanHerpes SimpleksellenjapBelum ada peringkat
- Meniere's DiseaseDokumen28 halamanMeniere's DiseaseellenjapBelum ada peringkat
- AntipsikosisDokumen10 halamanAntipsikosisellenjapBelum ada peringkat
- LeptospirosisDokumen18 halamanLeptospirosisellenjapBelum ada peringkat
- Profilaksis INH Pada TB-HIVDokumen8 halamanProfilaksis INH Pada TB-HIVellenjapBelum ada peringkat
- Gizi Sirosis HepatisDokumen17 halamanGizi Sirosis HepatisellenjapBelum ada peringkat
- Referat SkabiesDokumen18 halamanReferat SkabiesellenjapBelum ada peringkat
- MeningitisDokumen20 halamanMeningitisellenjapBelum ada peringkat