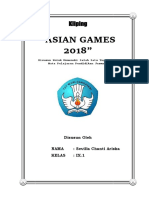Analisis Dampak Lingkungan 2
Analisis Dampak Lingkungan 2
Diunggah oleh
DindaHak Cipta:
Format Tersedia
Anda mungkin juga menyukai
- LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Konfigurasi Gateway 2Dokumen28 halamanLAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Konfigurasi Gateway 2Black Memories100% (1)
- Laporan Perjalanan Museum Lampung & Pantai KlaraDokumen24 halamanLaporan Perjalanan Museum Lampung & Pantai KlaraBlack Memories100% (2)
- Kabupaten PringsewuDokumen5 halamanKabupaten PringsewuBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Karya Tulis Ilmiah Kebersihan Lingkungan Sekolah 02Dokumen16 halamanKarya Tulis Ilmiah Kebersihan Lingkungan Sekolah 02Black Memories100% (1)
- Kabupaten Aceh BaratDokumen5 halamanKabupaten Aceh BaratBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Kliping ASIAN GAMES 3Dokumen17 halamanKliping ASIAN GAMES 3Black Memories0% (1)
- Adanya Teks EksposisiDokumen7 halamanAdanya Teks EksposisiBlack MemoriesBelum ada peringkat
- LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Windows XPDokumen27 halamanLAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Windows XPBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Biografi Wali SongoDokumen4 halamanBiografi Wali SongoBlack MemoriesBelum ada peringkat
- LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Cara Bongkar Printer Canon Pixma IP2770Dokumen23 halamanLAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Cara Bongkar Printer Canon Pixma IP2770Black Memories100% (2)
- Laporan Praktek Kerja Industri Asam TraneksmatDokumen28 halamanLaporan Praktek Kerja Industri Asam TraneksmatBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Laporan KI PT. Intech Anugrah IndonesiaDokumen17 halamanLaporan KI PT. Intech Anugrah IndonesiaBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Alat Musik Tradisional Provinsi PapuaDokumen9 halamanAlat Musik Tradisional Provinsi PapuaBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Bab 5 Pangkat Tak SebenarnyaDokumen11 halamanBab 5 Pangkat Tak SebenarnyaBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Aksara LampungDokumen2 halamanAksara LampungBlack Memories100% (2)
- Kliping ASIAN GAMES 2018Dokumen24 halamanKliping ASIAN GAMES 2018Black MemoriesBelum ada peringkat
- Alat Fitnes Dan KegunaanyaDokumen20 halamanAlat Fitnes Dan KegunaanyaBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Aliran Seni Rupa NATURALISMEDokumen8 halamanAliran Seni Rupa NATURALISMEBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Budidaya KentangDokumen12 halamanBudidaya KentangBlack MemoriesBelum ada peringkat
- LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen)Dokumen25 halamanLAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen)Black MemoriesBelum ada peringkat
- CerpenDokumen2 halamanCerpenBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Pengaruh Panjang Stek Dan Pemberian Zat PengatuiDokumen84 halamanPengaruh Panjang Stek Dan Pemberian Zat PengatuiBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Aksara LampungDokumen2 halamanAksara LampungBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Alkisah Pada Suatu HariDokumen13 halamanAlkisah Pada Suatu HariBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Putri Salju Dan Tujuh KurcaciDokumen10 halamanPutri Salju Dan Tujuh KurcaciBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Laporan Karya Wisata Di BMKG PahawangDokumen21 halamanLaporan Karya Wisata Di BMKG PahawangBlack Memories100% (1)
- Editing Dalam Microsoft WordDokumen22 halamanEditing Dalam Microsoft WordBlack MemoriesBelum ada peringkat
- LAPORAN PERJALANAN Museum Lampung Dan KlaraDokumen20 halamanLAPORAN PERJALANAN Museum Lampung Dan KlaraBlack Memories50% (2)
- Alat Reproduksi Pria Dan FungsinyaDokumen5 halamanAlat Reproduksi Pria Dan FungsinyaBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Laporan Karya Wisata Di BMKG PahawangDokumen21 halamanLaporan Karya Wisata Di BMKG PahawangBlack Memories100% (1)
Analisis Dampak Lingkungan 2
Analisis Dampak Lingkungan 2
Diunggah oleh
DindaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Analisis Dampak Lingkungan 2
Analisis Dampak Lingkungan 2
Diunggah oleh
DindaHak Cipta:
Format Tersedia
Tugas Mandiri
Psikologi Lingkungan
DAMPAK-DAMPAK LINGKUNGAN
Disusun oleh :
Nama : AHMAD AGUNG
Kelas :
NPM : 11130033
Prodi : BK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2012
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai
dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat
perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap
lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah
aspek Abiotik, Biotik, danKultural. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan
Pemerintah No. 32 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup.
Dokumen AMDAL terdiri dari :
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-
ANDAL)
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
AMDAL digunakan untuk:
Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan
hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan
Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha
dan atau kegiatan
Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup
Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu
rencana usaha dan atau kegiatan
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:
Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan masyarakat
yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk
keputusan dalam proses AMDAL.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan atau
menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib
AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib
AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
11 Tahun 2006
Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib
menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 86 Tahun 2002
Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai
dengan Permen LH NO. 08/2006
Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008
Pencemaran Air
Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat
penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas
manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus
kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain
mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam
fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau,
sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum,
sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya
berpotensi sebagai objek wisata.
A. Penyebab
Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki
karakteristik yang berbeda-beda.
Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi.
Sampah organik seperti air comberan (sewage) menyebabkan peningkatan
kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada
berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh
ekosistem.
Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya
seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Air
limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh
pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.
Seperti limbah pabrik yg mengalir ke sungai seperti di sungai citarum
pencemaran air oleh sampah
Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan
B. Dampak Pencemaran Air
Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air
minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan
danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Di badan air,
sungai dan danau, nitrogen dan fosfat (dari kegiatan pertanian) telah
menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali (eutrofikasi
berlebihan). Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen, yang
seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, menjadi
berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi mereka menyedot
lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati, dan aktivitas bakteri
menurun.
Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi atas 4 kelompok, yaitu :
Dampak terhadap kehidupan biota air
Dampak terhadap kualitas air tanah
Dampak terhadap kesehatan
Dampak terhadap estetika lingkungan
C. Pencegahan
Untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran air, dalam aktivitas kita
dalam memenuhi kebutuhan hidup hendaknya tidak menambah terjadinya
bahan pencemar antara lain tidak membuang sampah rumah tangga, sampah
rumah sakit, sampah/limbah industri secara sembarangan, tidak membuang ke
dalam air sungai, danau ataupun ke dalam selokan. Tidak menggunakan pupuk
dan pestisida secara berlebihan, karena sisa pupuk dan pestisida akan
mencemari air di lingkungan tanah pertanian. Tidak menggunakan deterjen
fosfat, karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti
enceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air.
Pencemaran air yang telah terjadi secara alami misalnya adanya jumlah
logam-logam berat yang masuk dan menumpuk dalam tubuh manusia, logam
berat ini dapat meracuni organ tubuh melalui pencernaan karena tubuh
memakan tumbuh-tumbuhan yang mengandung logam berat meskipun
diperlukan dalam jumlah kecil. Penumpukan logam-logam berat ini terjadi
dalam tumbuh-tumbuhan karena terkontaminasi oleh limbah industri. Untuk
menanggulangi agar tidak terjadi penumpukan logam-logam berat, maka
limbah industri hendaknya dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke
lingkungan.
KEBAKARAN HUTAN
A. Pengertian Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak, adalah
sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan
rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Penyebab umum termasuk
petir, kecerobohan manusia, dan pembakaran.
Musim kemarau dan pencegahan kebakaran hutan kecil adalah
penyebab utama kebakaran hutan besar.
Kebakaran hutan dalam bahasa Inggris berarti "api liar" yang berasal
dari sebuah sinonim dari Api Yunani, sebuah bahan seperti-napalm yang
digunakan di Eropa Pertengahan sebagai senjata maritim
B. Penyebab
Penyebab Kebakaran hutan, antara lain:
Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang
panjang.
Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok sembarangan
dan lupa mematikan api di perkemahan.
Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan
gunung berapi.
Tindakan yang disengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian atau
membuka lahan pertanian baru dan tindakan vandalisme.
Kebakaran di bawah tanah/ground fire pada daerah tanah gambut yang
dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.
C. Dampak Kebakaran Hutan
Dampak Terhadap Sosial, Budaya, dan Ekonomi. Kebakaran hutan
memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, budaya, dan
ekonomi yang diantaranya meliputi:
Terganggunya aktivitas sehari-hari; Asap yang diakibatkan oleh kebakaran
hutan secara otomatis mengganggu aktivitas manusia sehari-hari, apalagi
bagi yang aktivitasnya dilakukan di luar ruangan.
Menurunnya produktivitas; Terganggunya aktivitas manusia akibat
kebakaran hutan dapat mempengaruhi produktivitas dan penghasilan.
Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di dan sekitar hutan;
Selain itu, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari mengolah
hasil hutan, dengan terbakarnya hutan berarti hilang pula area kerja (mata
pencarian).
Meningkatnya hama; Kebakaran hutan akan memusnahkan sebagian
spesies dan merusak kesimbangan alam sehingga spesies-spesies yang
berpotensi menjadi hama tidak terkontrol. Selain itu, terbakarnya hutan
akan membuat sebagian binatang kehilangan habitat yang kemudian
memaksa mereka untuk keluar dari hutan dan menjadi hama seperti gajah,
monyet, dan binatang lain.
Terganggunya kesehatan; Kebakaran hutan berakibat pada pencemaran
udara oleh debu, gas SOx, NOx, COx, dan lain-lain dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap kesehatan manusia, antara lain infeksi saluran
pernafasan, sesak nafas, iritasi kulit, iritasi mata, dan lain-lain.
Tersedotnya anggaran negara; Setiap tahunnya diperlukan biaya yang
besar untuk menangani (menghentikan) kebakaran hutan. Pun untuk
merehabilitasi hutan yang terbakar serta berbagai dampak lain semisal
kesehatan masyarakat dan bencana alam yang diambilkan dari kas negara.
Menurunnya devisa negara. Hutan telah menjadi salah satu sumber devisa
negara baik dari kayu maupun produk-produk non kayu lainnya, termasuk
pariwisata. Dengan terbakarnya hutan sumber devisa akan musnah. Selain
itu, menurunnya produktivitas akibat kebakaran hutan pun pada akhirnya
berpengaruh pada devisa negara.
D. Cara Pencegahannya
Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dilakukan
antara lain
Memantapkan kelembagaan dengan membentuk dengan membentuk Sub
Direktorat Kebakaran Hutan dan Lembaga non struktural berupa
Pusdalkarhutnas, Pusdalkarhutda dan Satlak serta Brigade-brigade
pemadam kebakaran hutan di masing-masing HPH dan HTI;
Melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
Melengkapi perangkat keras berupa peralatan pencegah dan pemadam
kebakaran hutan;
Melakukan pelatihan pengendalian kebakaran hutan bagi aparat
pemerintah, tenaga BUMN dan perusahaan kehutanan serta masyarakat
sekitar hutan;
Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai Apel Siaga pengendalian
kebakaran hutan;
Pemberian pembekalan kepada pengusaha (HPH, HTI, perkebunan dan
Transmigrasi), Kanwil Dephut, dan jajaran Pemda oleh Menteri Kehutanan
dan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan
Upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan selama ini
ternyata belum memberikan hasil yang optimal dan kebakaran hutan masih
terus terjadi pada setiap musim kemarau. Kondisi ini disebabkan oleh
berbagai faktor antara lain:
Kemiskinan dan ketidak adilan bagi masyarakat pinggiran atau dalam
kawasan hutan.
Kesadaran semua lapisan masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih
rendah.
Kemampuan aparatur pemerintah khususnya untuk koordinasi,
memberikan penyuluhan untuk kesadaran masyarakat, dan melakukan
upaya pemadaman kebakaran semak belukar dan hutan masih rendah.
Upaya pendidikan baik formal maupun informal untuk penanggulangan
kebakaran hutan belum memadai.
TANAH LONGSOR
Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi
yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan
jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian
longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu.
Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material
sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya
material tersebut.
A. Faktor Penyebab Tanah Longsor
Umumnya, timbulnya tanah longsor dipicu oleh hujan lebat. Lereng
gunung yang gundul dan rapuhnya bebatuan dan kondisi tanah yang tidak
stabil membuat tanah-tanah ini tidak mampu menahan air di saat terjadi hujan
lebat. Akan tetapi, tanah longsor juga bisa ditimbulkan oleh aktivitas gunung
berapi atau gempa.
Selain faktor di atas, faktor lain yang memicu terjadinya tanah longsor
adalah erosi akibat sungai dan gelombang laut menciptakan lereng yang
curam. Bahkan petir, getaran mesin, dan penggunaan bahan peledak juga
dapat menimbulkan tanah longsor.
1. Hujan
Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November
seiring meningkatnya intensitas hujan. Musim kering yang panjang akan
menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah
besar. Muncul-lah pori-pori atau rongga tanah, kemudian terjadi retakan
dan rekahan tanah di permukaan. Pada saat hujan, air akan menyusup ke
bagian yang retak. Tanah pun dengan cepat mengembang kembali. Pada
awal musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu
singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena
melalui tanah yang merekah itulah, air akan masuk dan terakumulasi di
bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Apabila ada
pepohonan di permukaan, pelongsoran dapat dicegah karena air akan
diserap oleh tumbuhan. Akar tumbuhan juga berfungsi sebagai pengikat
tanah.
2. Lereng terjal
Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong.
Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air
laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor
adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya
mendatar.
3. Tanah yang kurang padat dan tebal
Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat
dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng > 220. Tanah jenis
ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi
hujan. Selain itu, jenis tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah
karena menjadi lembek jika terkena air dan pecah jika udara terlalu panas.
4. Batuan yang kurang kuat
Pada umumnya, batuan endapan gunungapi dan batuan sedimen
berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung kurang
kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah jika mengalami proses
pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor apabila terdapat
pada lereng yang terjal.
5. Getaran
Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempabumi, ledakan,
getaran mesin, dan getaran lalulintas kendaraan. Akibat yang
ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah
menjadi retak.
B. Dampak
Di daerah yang terjal, kecepatan luncuran tanah longsor dapat mencapai
75 km/jam sehingga sulit bagi seseorang untuk menyelamatkan diri. Itulah
sebabnya ketika tanah longsor terjadi, banyak rumah dan penduduk, binatang,
fasilitas umum yang tertimbun longsoran. Bencana ini pun banyak memakan
korban jiwa.
Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menanggulanginya dengan
menghindari penyebab timbulnya tanah longsor. Caranya dengan tidak
menebangi hutan, menanam tumbuhan berakar kuat seperti lamtoro, bambu,
akar wangi, dan tumbuhan lainnya pada lereng yang gundul, membuat saluran
air hujan, memeriksa keadaan tanah secara rutin dan berkala, membangun
tembok penahan di lereng yang terjal, juga mengukur tingkat kederasan air
hujan.
Bencana alam/tanah longsor dapat mengakibatkan dampak yang
merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur
dapat mengganggu aktivitas sosial, dampak dalam bidang sosial mencakup
kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan kekacauan
komunitas, sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan
yang melindungi daratan.
C. Pencegahan
Pencegahan Terjadinya Bencana Tanah Longsor
Jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas di
dekat pemukiman
Buatlah terasering (sengkedan) [ada lereng yang terjal bila membangun
permukiman
Segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke
dalam tanah melalui retakan.
Jangan melakukan penggalian di bawah lereng terjal.
Jangan menebang pohon di lereng
Jangan membangun rumah di bawah tebing.
Jangan mendirikan permukiman di tepi lereng yang terjal
Tahapan Mitigasi Bencana Tanah Longsor
Pemetaan
Menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam
geologi di suatu wilayah, sebagai masukan kepada masyarakat dan atau
pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sebagai data dasar untuk
melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana.
Penyelidikan
Mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana sehingga dapat
digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan rencana
pengembangan wilayah.
Pemeriksaan
Melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana, sehingga
dapat diketahui penyebab dan cara penaggulangannya.
Pemantauan
Pemantauan dilakukan di daerah rawan bencana, pada daerah strategis
secara ekonomi dan jasa, agar diketahui secara dini tingkat bahaya, oleh
pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.
Sosialisasi
Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Provinsi /Kabupaten /Kota
atau Masyarakat umum, tentang bencana alam tanah longsor dan akibat
yang ditimbulkannnya. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara antara
lain, mengirimkan poster, booklet, dan leaflet atau dapat juga secara
langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintah
Pemeriksaan bencana longsor
Bertujuan mempelajari penyebab, proses terjadinya, kondisi bencana dan
tata cara penanggulangan bencana di suatu daerah yang terlanda bencana
tanah longsor.
Anda mungkin juga menyukai
- LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Konfigurasi Gateway 2Dokumen28 halamanLAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Konfigurasi Gateway 2Black Memories100% (1)
- Laporan Perjalanan Museum Lampung & Pantai KlaraDokumen24 halamanLaporan Perjalanan Museum Lampung & Pantai KlaraBlack Memories100% (2)
- Kabupaten PringsewuDokumen5 halamanKabupaten PringsewuBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Karya Tulis Ilmiah Kebersihan Lingkungan Sekolah 02Dokumen16 halamanKarya Tulis Ilmiah Kebersihan Lingkungan Sekolah 02Black Memories100% (1)
- Kabupaten Aceh BaratDokumen5 halamanKabupaten Aceh BaratBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Kliping ASIAN GAMES 3Dokumen17 halamanKliping ASIAN GAMES 3Black Memories0% (1)
- Adanya Teks EksposisiDokumen7 halamanAdanya Teks EksposisiBlack MemoriesBelum ada peringkat
- LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Windows XPDokumen27 halamanLAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Windows XPBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Biografi Wali SongoDokumen4 halamanBiografi Wali SongoBlack MemoriesBelum ada peringkat
- LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Cara Bongkar Printer Canon Pixma IP2770Dokumen23 halamanLAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI Cara Bongkar Printer Canon Pixma IP2770Black Memories100% (2)
- Laporan Praktek Kerja Industri Asam TraneksmatDokumen28 halamanLaporan Praktek Kerja Industri Asam TraneksmatBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Laporan KI PT. Intech Anugrah IndonesiaDokumen17 halamanLaporan KI PT. Intech Anugrah IndonesiaBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Alat Musik Tradisional Provinsi PapuaDokumen9 halamanAlat Musik Tradisional Provinsi PapuaBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Bab 5 Pangkat Tak SebenarnyaDokumen11 halamanBab 5 Pangkat Tak SebenarnyaBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Aksara LampungDokumen2 halamanAksara LampungBlack Memories100% (2)
- Kliping ASIAN GAMES 2018Dokumen24 halamanKliping ASIAN GAMES 2018Black MemoriesBelum ada peringkat
- Alat Fitnes Dan KegunaanyaDokumen20 halamanAlat Fitnes Dan KegunaanyaBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Aliran Seni Rupa NATURALISMEDokumen8 halamanAliran Seni Rupa NATURALISMEBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Budidaya KentangDokumen12 halamanBudidaya KentangBlack MemoriesBelum ada peringkat
- LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen)Dokumen25 halamanLAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen)Black MemoriesBelum ada peringkat
- CerpenDokumen2 halamanCerpenBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Pengaruh Panjang Stek Dan Pemberian Zat PengatuiDokumen84 halamanPengaruh Panjang Stek Dan Pemberian Zat PengatuiBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Aksara LampungDokumen2 halamanAksara LampungBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Alkisah Pada Suatu HariDokumen13 halamanAlkisah Pada Suatu HariBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Putri Salju Dan Tujuh KurcaciDokumen10 halamanPutri Salju Dan Tujuh KurcaciBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Laporan Karya Wisata Di BMKG PahawangDokumen21 halamanLaporan Karya Wisata Di BMKG PahawangBlack Memories100% (1)
- Editing Dalam Microsoft WordDokumen22 halamanEditing Dalam Microsoft WordBlack MemoriesBelum ada peringkat
- LAPORAN PERJALANAN Museum Lampung Dan KlaraDokumen20 halamanLAPORAN PERJALANAN Museum Lampung Dan KlaraBlack Memories50% (2)
- Alat Reproduksi Pria Dan FungsinyaDokumen5 halamanAlat Reproduksi Pria Dan FungsinyaBlack MemoriesBelum ada peringkat
- Laporan Karya Wisata Di BMKG PahawangDokumen21 halamanLaporan Karya Wisata Di BMKG PahawangBlack Memories100% (1)