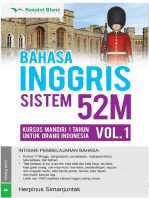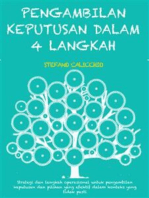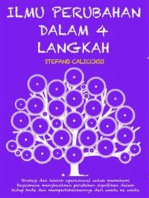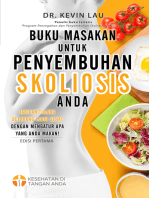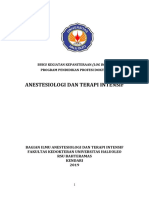CSL1 PDF
CSL1 PDF
Diunggah oleh
Dewi Tri AJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
CSL1 PDF
CSL1 PDF
Diunggah oleh
Dewi Tri AHak Cipta:
Format Tersedia
Buku Panduan CSL 1 2017
BUKU PANDUAN
CLINICAL SKILL LABORATORY
SEMESTER 1
Edisi Ke-4
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Jln. Prof Soemantri Bojonegoro No.1
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 1
Buku Panduan CSL 1 2017
Bandar Lampung-Indonesia
Telp / Fax : (0721) 77665
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
………………………………………………………………………………………………………………
Buku Panduan Clinical Skill Laboratory
Semester 1
Edisi Ke-4
Cetakan Kedua | 2017
Diterbitkan pertama kali oleh :
Tim Pengembangan KBK (Bagian CSL) Fakultas Kedokteran
Universitas Lampung
Dicetak di Bandar Lampung
………………………………………………………………………………………………………
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 2
Buku Panduan CSL 1 2017
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku tanpa izin tertulis dari penyusun.
TIM PENYUSUN
..:: Editor ::..
dr. Novita Carolia, M.Sc
dr. Ryan Falamy
..:: Kontributor ::..
dr. T.A. Larasati, M.Kes
dr. Nurul Islami, M.Kes
dr. Susianti, M.Sc
dr. Hanna Mutiara
dr. Dian Isti Anggraeni
dr. Iswandi Darwis
dr. Novita Carolia, M.Sc
dr. Muhammad Aditya
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 3
Buku Panduan CSL 1 2017
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan
kekuatan serta kemudahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan buku
panduan Clinical Skill Laboratorium (CSL) Semeter 1 ini. Buku ini disusun sebagai
panduan bagi mahasiswa maupun instruktur dala proses pembelajaran CSL
pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Fakultas Kedokteran Universitas
Lampung (FK Unila) semester 1 tahun ajaran 2017-2018.
Penyajian yang sama dengan tahun sebelumnya dimana CSL tahun
ajaran 2017-2018 ini tidak masuk ke dalam blok yang berjalan. Selain itu revisi
kurikulum tahun 2012 juga berefek pada materi CSL yang disajikan. Akan tetapi,
materi yang diberikan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pada semester 1 ini, mahasiswa diperkenalkan dengan CSL yang mencakup
ketrampilan komunikasi sambung rasa percaya diri dan hubungan dokter
pasien. Pada pemeriksaan fisik diberikan materi mengenai General Survey dan
Vital Sign. Laboratorium memberikan kontribusi pengenalan mikroskop dan
penulisan laporan ilmiah. Sedangkan keterampilan prosedural diberikan materi
mengenai pengenalan alat bedah minor dan hecting dasar, prinsip sterilitas, dan
cuci tangan WHO. Buku panduan ini disusun dengan mengacu pada kompetensi
yang harus dimiliki oleh seorang dokter yang tertuang dalam Standar
Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012.
Penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
konributor yang telah memberikan masukan demi memperkaya materi buku ini,
pengelola KBK PFK unila, maupun pihak-pihak lain yang turut membantu hingga
selesainya buku ini.
Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, semoga buku
ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kesempurnaan
penyempurnaan berikutnya kritik dan saran dapat diharapkan.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 4
Buku Panduan CSL 1 2017
Bandar Lampung, 2017
Editor
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................
Daftar Isi .......................................................................................................
Daftar Materi Clinical Skills Lab ....................................................................
Regulasi CSL ..................................................................................................
Lesson Plan & Level of Competences............................................................
CSL 1. Sambung Rasa dan Percaya Diri ........................................................
CSL 1. Hubungan Dokter – Pasien dan kerangka anamnesis .......................
CSL 2. Cuci Tangan WHO ..............................................................................
CSL 3. General Survey ...................................................................................
CSL 4. Vital Sign ............................................................................................
CSL 5. Pengenalan alat bedah minor dan prinsip sterilitas ..........................
CSL 6. Pengenalan Mikroskop ......................................................................
CSL 7. Pemeriksaan Saraf Kranial ................................................................
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 5
Buku Panduan CSL 1 2017
CSL 8. Pemeriksaan Motoris dan Sensoris ..................................................
CSL 9. Pemeriksaan Muskuloskeletal dan ROM ..........................................
CSL 10 Refleks Fisiologis dan Patologis .......................................................
CSL 11 Pengenalan Rekam Medis ................................................................
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 6
Buku Panduan CSL 1 2017
DAFTAR MATERI CLINICAL SKILLS LAB (CSL)
SEMESTER 1
Semester : 1
Angkatan Tahun : 2017 Tahun Ajaran : 2017/2018
Jenis Keterampilan CSL
No Judul CSL Pemeriksaan
Komunikasi Prosedural Laboratorium
Fisik
1 Sambung Rasa Percaya Diri √ - - -
2 Hubungan Dokter-Pasien √ - - -
3 Kerangka Anamnesis √ - - -
4 Cuci Tangan WHO - - √ -
Pengenalan alat bedah
5 - - √ -
minor
6 General Survey - √ - -
7 Vital Sign - √ - -
8 Pemeriksaan Saraf Kranial - √ - -
9 Pengenalan Mikroskop - - - √
Pemeriksaan Motoris dan
10 - √ - -
Sensoris
Pemeriksaan
11 - √ - -
Muskuloskeletal dan ROM
Refleks Fisiologis dan
12 - √ - -
Patologis
13 Pengenalan Rekam Medis √ - - -
14 Prinsip Sterilitas - - √ -
Per Kelompok
Kuliah Besar
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 7
Buku Panduan CSL 1 2017
REGULASI CSL
TATA TERTIB :
a. Tata tertib umum
1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti semua kegiatan blok CSL 3, yaitu :
• Latihan keterampilan klinik/ CSL, 2 kali seminggu ( Senin pukul
14.40 – 16.20 WIB dan Rabu pukul 08.40 – 10.20 WIB kecuali jika
ada libur nasional akan disesuaikan).
• Pretest, yang akan diberikan sebelum latihan CSL di pertemuan
pertama
• Inhal dan tugas, bila mahasiswa tidak lulus pretest
• Briefing OSCE dan remediasi
2. Berpakaian rapi
• Tidak diperbolehkan memakai kaus oblong, celana blue jeans,
sandal/sepatu sandal khusus mahasiswi tidak diperbolehkan
berbaju ketat, transparan dan tanpa lengan atau terlihat ketiak
serta harus memakai rok minimal di bawah lutut.
• Rambut harus rapi, tidak diperbolehkan berambut gondrong untuk
laki-laki
• Kuku harus pendek, bersih, dan tidak menggunakan cat kuku
3. Sopan santun dan etika
• Jujur dan bertanggung jawab
• Disiplin
• Tidak merokok di lingkungan kampus
• Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, NAPZA, alat-alat
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 8
Buku Panduan CSL 1 2017
yang tidak sesuai dengan tupoksi sebagai mahasiswa.
• Tidak diperbolehkan membuat kegaduhan
• Tidak diperbolehkan memalsukan tanda tangan PA atau para dosen
• Tidak diperbolehkan memalsukan dokumen
• Tidak diperkenankan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun
pada saat CSL dan OSCE.
4. Mentaati peraturan akademik FK Universitas Lampung dan peraturan
akademik Universitas Lampung
b. Tata tertib Khusus
1. Kegiatan CSL setiap topik terbagi atas 2 sesi.
2. Pada kegiatan CSL terdapat 2 buku, yakni Buku Panduan CSL dan Buku
Kegiatan CSL yang wajib dibawa setiap sesi.
3. Keikutsertaan 100%.
4. Harap hadir tepat waktu.
5. Jika terlambat ≤ 15 menit dapat mengikuti CSL dengan pre-test susulan di
ruang administrasi CSL dan nilai pre-test dikurangi 10 poin.
6. Jika terlambat >15 menit tidak diperkenankan mengikuti CSL.
7. Pada Sesi 1 akan dilakukan pre-test secara serentak dan dikumpulkan pada
instruktur penanggung jawab pre-test yang bertugas
8. Pelaksanaan pre-test dilakukan serentak di ruang CSL dengan instruktur
masing-masing, atau dikumpulkan di ruang tertentu untuk jenis
keterampilan tertentu seperti keterampilan Laboratorium
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 9
Buku Panduan CSL 1 2017
9. Saat pre-test mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kecurangan
seperti mencontek atau bekerjasama dengan temannya, dan akan langsung
ditarik lembar jawabannya dan jawaban dianulir.
10. Pada akhir sesi 1 akan diumumkan mahasiswa/i yang mendapat nilai pre-
test <70 dan penugasannya yang wajib dikumpulkan sebelum CSL sesi 2
pada instruktur penanggung jawab pre-test.
11. Jika tugas tidak dikumpulkan tepat waktu dan jika mendapat nilai tugas
<60 maka akan mendapatkan tugas ke-2.
12. Jika tugas 1 dan 2 tidak dikumpulkan dan atau nilai tugas ke-2 <60 maka
CSL yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
13. Pada Sesi 2 mahasiswa melakukan keterampilan klinik dengan dinilai oleh
rekannya dibawah pengawasan instruktur.
14. Penilaian dilakukan pada buku kegiatan mahasiswa dan ditandatangani
oleh instruktur saat pelaksanaan skills lab berlangsung sebagai bukti
otentik latihan serta tidak boleh disobek.
15. Nilai pada ceklist latihan terdapat nilai 0, 1, dan 2. Jika poin tersebut tidak
dikerjakan maka diberi nilai 0, jika dilakukan tetapi masih dengan
kekurangan (tidak sempurna) maka diberi nilai 1 dan jika dilakukan dengan
sempurna maka diberi nilai 2.
16. Nilai latihan diperinci sebagai berikut :
a. < 70% : Belum terampil
b. 70% – 85% : Terampil
c. > 85% : Sangat terampil
17. Dimana nilai latihan harus ≥ 70%. Apabila <70% maka mahasiswa yang
bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti Belajar Mandiri sebelum OSCE.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 10
Buku Panduan CSL 1 2017
18. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan CSL baik sesi 1 atau ke-2 dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (forced majeur) harus
mengajukan surat permohonan kepada Pimpinan Program Studi untuk
dapat diadakan CSL susulan sebelum Ujian OSCE diadakan.
19. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan CSL, tanpa alasan yang jelas/
tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat mengikuti Ujian OSCE
20. Mahasiswa yang tidak lengkap kegiatan latihannya tidak dapat mengikuti
Ujian OSCE.
21. Pada halaman terakhir Buku Kegiatan CSL terdapat Lembar Rekapitulasi
Nilai CSL yang harus diparaf setiap selesai latihan oleh instruktur yang
bertugas.
22. Pada akhir blok, rekapitulasi nilai tersebut akan diperiksa dan diberikan
rekomendasi layak/tidaknya mengikuti OSCE oleh PJ CSL blok yang
bersangkutan.
23. Mahasiswa/i yang tidak menghadiri CSL (salah satu atau kedua kegiatan)
maka harus mendapatkan rekomendasi dari ketua program studi
kedokteran unila untuk mengikuti CSL susulan dengan menanggung biaya
pelaksanaan CSL tersebut (seperti biaya BHP dan pemeliharaan alat)
24. Hal-hal yang belum diatur dalam regulasi ini akan ditetapkan kemudian
Bandar Lampung, September 2017
Tim CSL
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 11
Buku Panduan CSL 1 2017
DAFTAR KETERAMPILAN CSL SEMESTER 1
No Materi Jenis Level Pemberian
Keterampilan kompetensi materi
1 Sambung Rasa Percaya Komunikasi 4 Perkelompok
Diri
2 Hubungan Dokter- Komunikasi 4 Perkelompok
Pasien
3 General Survey Pemeriksaan 4 Perkelompok
fisik
4 Vital Sign Pemeriksaan 4 Perkelompok
fisik
5 Pengenalan Mikroskop Laboratorium 4 Perkelompok
6 Pengenalan alat bedah Prosedural 4 Kuliah besar
minor dan hecting dasar
7 Pemeriksaan Saraf Pemeriksaan 4 Perkelompok
Kranial fisik
8 Patient safety Komunikasi 4 Kuliah besar
9 Pemeriksaan Motoris Pemeriksaan 4 Perkelompok
dan Kekuatan Otot fisik
10 Cuci tangan WHO Prosedural 4 Kuliah besar
11 Pemeriksaan Pemeriksaan 4 Perkelompok
Muskuloskeletal dan fisik
ROM
LEVEL OF COMPETENCE
Level Kompetensi 1 Mengetahui dan menjelaskan
Level Kompetensi 2 Pernah melihat / didemonstrasikan
Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah
Level Kompetensi 3
supervisi
Level Kompetensi 4 Mampu melakukan secara mandiri
LESSON PLAN CSL SESI 1
No Kegiatan Alokasi Waktu
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 12
Buku Panduan CSL 1 2017
1 Perkenalan instruktur dan absensi mahasiswa/i 5 menit
2 Pre Test 10 menit
3 Overview materi 5 menit
4 Demonstrasi 10 menit
5 Mahasiswa/i berlatih 60 menit
6 Feed back dan penutup 10 menit
LESSON PLAN CSL SESI 2
No Kegiatan Alokasi Waktu
1 Perkenalan instruktur dan absensi mahasiswa/i 5 menit
2 Persiapan dan pengaturan latihan 5 menit
3 Penilaian terhadap mahasiswa yang berlatih 80 menit
4 Feed back dan penutup 10 menit
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 13
Buku Panduan CSL 1 2017
..: SAMBUNG RASA DAN PERCAYA DIRI
dr. T.A. Larasati, M. Kes | dr. Hanna Mutiara
A. TEMA
Sambung Rasa dan Percaya Diri
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sambung rasa dan
percaya diri.
C. ALAT DAN BAHAN
• Kursi dokter dan pasien
• Meja dokter
D. SKENARIO
Zaskia, 19 tahun, datang kepada anda yang sedang bertugas di klinik
dokter keluarga. Pasien merasa cemas dan sulit tidur selama menghadapi
ujian semester. Zaskia mengaku keluhan ini sering muncul bila menjelang
ujian. Anda sebagai dokter keluarga diharapkan dapat melakukan sambung
rasa dengan baik dan percaya diri.
E. DASAR TEORI
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 14
Buku Panduan CSL 1 2017
1. Sambung Rasa
Keterampilan komunikasi sangat penting dimiliki oleh dokter yang
dalam tugasnya harus mengumpulkan informasi dari seseorang atau
sekelompok orang. Dengan komunikasi yang sederhana, cepat, dan
efektif maka akan diperoleh informasi yang akurat. Banyak kelemahan
hasil anamnesis (wawancara) disebabkan keterampilan komunikasi
yang kurang memadai serta sikap dokter yang kurang memperhatikan
aspek psikologis pasien. Atas kenyataan tersebut, maka keterampilan
komunikasi akan sangat membantu dalam melakukan tugas sebagai
dokter.
Komunikasi secara garis besar adalah proses penyampaian sinyal dan
pesan. Komunikasi dalam dunia medis berbeda dengan komunikasi
dalam bidang lain dilihat dari tiga aspek:
a. Berkaitan dengan hal yang paling penting dalam kehidupan yaitu
kesehatan. Setiap orang dalam masyarakat pada semua tahapan
dan tingkat usia, sangat memperhatikan dengan serius apa yang
dikatakan oleh dokter.
b. Dalam komunikasi medis melibatkan lebih besar emosi alamiah
dan bersifat personal.
c. Secara sosial komunikasi dalam dunia medis mengizinkan profesi
medis menyentuh tubuh pasien untuk tujuan pemeriksaan.
Adapun tujuan komunikasi dengan pasien mencakup tiga hal:
a. Membina hubungan berdasarkan rasa percaya,
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 15
Buku Panduan CSL 1 2017
b. Untuk mendapatkan informasi dari pasien,
c. Untuk menyampaikan informasi kepada pasien.
Interaksi yang baik antara dokter dan pasien membuat pasien merasa
lebih nyaman ketika memberikan informasi dan itu menjadi dasar
hubungan dokter – pasien, karena dalam keadaan sakit dapat
membuat pasien merasa terisolasi dan segan. Perasaan
ketersambungan dengan dokter, disimak dan dipahami akan
mengurangi perasaan terisolasi tersebut. Perasaan ini adalah inti dari
penyembuhan (Bickley, 2007). Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam
komunikasi dokter-pasien perlu dilakukan sambung rasa.
Sambung rasa adalah komunikasi yang terjadi apabila gagasan dan
perasaan yang disampaikan pembawa pesan dapat menggugah dan
menggerakkan hati penerima pesan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
Sambung rasa merupakan suatu tahap komunikasi yang harus
diciptakan terlebih dahulu agar hal-hal yang menghambat proses
komunikasi dapat dihindari. Dengan terciptanya sambung rasa antara
dokter dan pasien, maka pasien akan senang dan tanpa beban
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dokter. Dalam keadaan
seperti tersebut, pasien akan memberikan jawaban dengan lancar dan
akurat, sehingga dipeoleh data informasi yang sebenarnya.
Agar tercipta adanya sambung rasa antara dokter dan pasien, maka
dokter harus berusaha membina sikap serta pandangan tertentu
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 16
Buku Panduan CSL 1 2017
terhadap pasien, yaitu agar :
a. Pasien mempercayai dokter, bahwa dokter tidak akan membuka
rahasia pasien kepada siapapun.
Misalnya : “Bapak/Ibu tidak perlu khawatir, semua yang bapak/ibu
sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya, jadi saya harapkan
bapak/ibu dapat memberikan informasi yang sejujur-jujurnya”
b. Pasien memahami bahwa hasil wawancara akan digunakan demi
kepentingan serta kebaikan pasien.
Misalnya : ”informasi yang bapak/ibu berikan sangat penting untuk
penegakkan diagnosis penyakit bapak/ibu dan pemberian terapi
yang sesuai dengan penyakit bapak/ibu.”
c. Pasien merasakan bahwa dokter berempati kepadanya (bukan
merasa iba atas penderitaan pasien). Empati bukan simpati, empati
berarti memahami situasi dari sudut pandang orang yang
mengalaminya, sedangkan simpati mengalami emosi yang sama
dengan orang lain. Dokter dapat melakukan refleksi isi dan refleksi
perasaan untuk menunjukkan empati. Refleksi isi merupakan
refleksi dari informasi yang disampaikan oleh pasien. sedangkan
refleksi perasaan merupakan refleksi dari perasaan pasien.
d. Pasien merasa dokter memberi kesempatan kepadanya untuk
mengemukakan pendapat/informasi ataupun bertanya dengan
leluasa.
Misalnya: “Apakah dari penejelasan saya ada yang kurang jelas,
atau ada hal yang bapak/ibu yang ingin tanyakan?”
e. Pasien merasa wawancara ini merupakan percakapan yang
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 17
Buku Panduan CSL 1 2017
dilakukan individu yang sederajat (bukan interogasi).
2. Percaya diri
Percaya diri adalah yakin benar atau memastikan akan kemampuan
diri sendiri. Percaya diri seorang dokter adalah keadaan mental yang
yakin akan kemampuan dirinya dalam menjalankan profesi sesuai
standar kompetensi dokter. Agar dapat tampil percaya diri, perlu
dilakukan beberapa hal:
a. Mempersiapkan dengan baik segala sesuatu berkaitan dengan hal
yang akan dilakukan.
b. Melakukan sesuatu dengan tenang dan tidak terburu-buru.
c. Bicara dengan alur yang teratur, tidak berbelit-belit dan tidak
gugup.
d. Melakukan kontak mata dengan lawan bicara (pasien). Dengan
kontak mata, tidak hanya membantu membangun rasa percaya
diri, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa percaya pasien pada
dokter.
3. Komunikasi Non Verbal
Komunikasi non verbal adalah pemberian pesan kepada orang lain
dengan menggunakan bahasa tubuh (gestur). Beberapa bahasa tubuh
dokter maupun pasien yang harus diperhatikan dalam sambung rasa :
• Wajah menggambarkan emosi seseorang: marah, sedih, bahagia
• Bahu tinggi bila tegang, turun bila relax atau santai
• Posisi kepala tinggi menunjukkan keterbukaan, tertarik dan
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 18
Buku Panduan CSL 1 2017
dapat menguasai keadaan; rendah menunjukkan keraguan,
kelemahan, takut atau terancam.
• Postur tubuh tegap menunjukkan percaya diri.
• Gerakan tangan gerakan tangan ke hidung mengekspresikan
ketidakpastian, gerakan tangan ke mulut mengindikasikan ragu
tehadap apa yang diucapkan
• Kaki duduk di kursi dengan telapak kaki dalam posisi “siap lari”
menunjukkan ketidaktertarikan.
F. PROSEDUR
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam sambung rasa adalah:
1. Berpenampilan yang sederhana, rapi, bersih, dan tepat.
2. Memberikan salam dan membuat pasien merasa disambut dengan
baik.
3. Menunjukkan tempat duduknya, dan memakai bahasa yang sesuai
antara keadaan dokter dan pasien.
4. Memperkenalkan diri.
5. Menanyakan identitas pasien.
6. Menyampaikan kalimat sambutan, tergantung apakah pasien
merupakan pasien baru, pasien follow-up atau pasien lama yang
datang untuk konsultasi kembali.
7. Memperlihatkan wajah yang ramah, bersahabat, serta sopan santun.
8. Menciptakan suasana wawancara yang santai dan menyenangkan.
9. Melakukan kontak mata, jangan ada hal yang mengganggu, seperti
komputer yang menghalangi pandangan dokter kepada pasien.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 19
Buku Panduan CSL 1 2017
10. Bahasa tubuh dokter, merupakan komunikasi non verbal, akan
memperlihatkan sikap dokter terhadap pasien
G. REFERENSI
1. Bickley, Lynn. S. BATES Guide to Physical Examination and History
Taking (Ninth Edition). Lippincott Williams & Wilkins
2. Gan, Goh Lee, at all. 2004. A Primer On Family Medicine Practice,
Singapore International Foundation, Singapore.
3. Azwar Azrul. 1996. Pengantar Pelayanan Dokter Keluarga.Yayasan
Penerbit IDI. Jakarta
4. Mc Whinney. 1989. A Text Book of Family Medicine. Oxford
University.New York
1. CHECK LIST KETERAMPILAN SAMBUNG RASA
Skor Feed Back
No Aspek
0 1 2
I INTERPERSONAL
1 Berpakaian rapi, bersih dan tepat
2 Berkomunikasi non verbal yang
mendukung sambung rasa
II CONTENT
3 Mengucapkan salam pada awal
wawancara
4 Menunjukkan tempat duduk dan
meminta pasien duduk berhadapan
5 Memperkenalkan diri
6 Menanyakan identitas
7 Menyampaikan kalimat sambutan
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 20
Buku Panduan CSL 1 2017
sebagai pembuka
8 Melakukan kontak mata
9 Tersenyum, bersikap terbuka, ramah
dan sopan santun
10 Menyampaikan informed consent
III PROFESIONALISM
11 Melakukan dengan penuh percaya
diri
TOTAL
Nilai = ------------- x 100% = …………
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 21
Buku Panduan CSL 1 2017
..: HUBUNGAN DOKTER-PASIEN
dr. Nurul Islamy, M.Kes | dr.Hanna Mutiara
A. TEMA
Hubungan Dokter-Pasien
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Tujuan instruksional umum
Mahasiswa mampu membina hubungan Dokter-Pasien dengan baik
2. Tujuan instruksional khusus
Setelah mempelajari keterampilan klinik ini diharapkan mahasiswa
mampu:
a. Melakukan komunikasi interpersonal dengan pasien dalam lingkup
bidang kesehatan.
b. Menempatkan diri sejajar dengan pasien (pasien dan keluarganya
adalah mitra kerja).
c. Membina hubungan yg terjadi antara dokter dengan pasien karena
adanya tanggung jawab & kewajiban profesi dokter terhadap
pasien.
d. Menjelaskan kedudukan dokter dan kedudukan pasien dalam
pelayanan kesehatan.
e. Menghormati hak-hak dan kewajiban baik pasien maupun dokter
f. Membina hubungan yang baik antara dokter dengan pasien secara
terus-menerus & berkesinambungan.
C. ALAT DAN BAHAN
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 22
Buku Panduan CSL 1 2017
1. Kursi (untuk dokter dan pasien)
2. Meja dokter
D. SKENARIO
Pak Rafi, 44 tahun, datang ke klinik anda dengan keluhan sakit kepala. Pak
Rafi cemas akan keluhannya karena sudah 3 hari tidak kunjung membaik
dengan obat warung. Pak Rafi memiliki riwayat darah tinggi kurang lebih
sudah 10 tahun namun tidak terkontrol dengan baik. Riwayat penyakit darah
tinggi dalam keluarga diderita oleh kedua orang tuanya, dan ibunya
meninggal karena stroke. Pak Rafi cemas apakah dirinya akan menderita
stroke sama seperti ibunya. Anda sebagai dokter keluarga diharapkan
mampu membina hubungan dokter-pasien dengan baik.
E. DASAR TEORI
Batasan
Batasan hubungan dokter pasien tidaklah mudah dirumuskan. Secara
sederhana dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara dokter
dengan pasien karena adanya tanggung jawab dan kewajiban profesi dokter
terhadap pasien. Tanggung jawab dan kewajiban profesi dokter terhadap
pasien tidak hanya terbatas pada waktu menyelenggarakan pelayanan
kedokteran saja, tetapi harus terus menerus dibina dan berkesinambungan.
Karakteristik
Dasar utama terbentuknya hubungan dokter pasien adalah karena adanya
tanggung-jawab dan kewajiban profesi. Hubungan yang terjadi tidak
terbatas hanya di bidang kesehatan saja, tetapi hampir semua aspek
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 23
Buku Panduan CSL 1 2017
kehidupan pasien. Ruang lingkup sangat luas serta ditambah ekspektasi
pasien yang sangat beraneka ragam menyebabkan peran dokter tidak hanya
tunggal, melainkan majemuk (ahli kesehatan, konselor, guru, teman).
Hubungan dokter pasien, terutama dokter keluarga berlangsung lama dan
mencakup banyak anggota keluarga (Koh et al, 1988; Mc Whinney, 1981).
Tujuan hubungan dokter pasien adalah demi kepentingan pasien dan sifat
hubungan:
1. Hubungan interpersonal
2. Hubungan administratif
Prinsip hubungan interpersonal dokter dan pasien:
o Berlandaskan rasa saling percaya
o Demi kepentingan pasien
o Memperhatikan hak dan kewajiban pasien
o Memperhatikan hak dan kewajiban dokter
o Melalui komunikasi efektif
Hak pasien
• Hak informasi: hak untuk mengetahui semua informasi yang
dibutuhkan.
• Hak akses: hak untuk memperoleh pelayanan tanpa dibedakan status
sosial, ekonomi dan budaya.
• Hak memilih: hak untuk memutuskan secara bebas penanggulangan
masalah yang dihadapinya.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 24
Buku Panduan CSL 1 2017
• Hak keamanan: hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan
efektif.
• Hak kerahasiaan: hak dijamin kerahasiaan informasi mengenai pasien.
• Hak privasi: hak mendapatkan privasi dalam pelayanan (konseling dan
pemeriksaan).
• Hak martabat: hak mendapat pelayanan yang manusiawi (dihargai dan
diperhatikan).
• Hak kenyamanan: hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam
pelayanan.
• Hak kesinambungan: hak untuk mendapatkan jaminan ketersediaan
sarana secara lengkap dan pelayanan berkesinambungan selama
diperlukan.
• Hak berpendapat: hak untuk menyatakan pendapat secara bebas.
Kewajiban pasien
• Memberikan keterangan yang benar / berterus terang.
• Menaati kemufakatan yang telah disepakati.
• Memenuhi aturan pada sarana pelayanan kesehatan.
• Memberi imbalan jasa.
• Menyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya.
Hak dokter
✓ Menolak bekerja di luar standar pelayanan medik.
✓ Menolak tindakan yang bertentangan dengan kode etik.
✓ Mengakhiri hubungan profesional dengan pasien.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 25
Buku Panduan CSL 1 2017
✓ Mendapatkan kehidupan pribadi (privacy).
✓ Memperoleh imbalan jasa.
✓ Menolak memberikan keterangan mengenai pasiennya.
Kewajiban dokter
✓ Bekerja sesuai standar profesi.
✓ Memberikan informed consent.
✓ Menolong pasien gawat darurat.
Langkah-langkah untuk dapat mewujudkan hubungan dokter pasien yang
baik:
a. Memahami diri sendiri
Langkah pertama adalah mencoba memahami diri sendiri yang
menyangkut kelebihan dan ataupun kekurangan yang dimiliki. Dengan
diketahuinya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki tersebut, dapatlah
disesuaikan sikap dan perilaku dokter, sehingga sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan pasien.
b. Meningkatkan komunikasi interpersonal
Meningkatkan kemampuan komunikasi bertujuan untuk dapat
mengasah diri sehingga dapat menjadi lebih sensitive (be sensitive),
dapat menerima (be accepting) serta bersifat sabar (be patient).
c. Memahami pasien seutuhnya
Dokter yang baik tidak hanya memperhatikan keluhan yang disampaikan
pasien dan ataupun organ tubuh yang sakit saja, tetapi memperhatikan
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 26
Buku Panduan CSL 1 2017
pasien sebagaimana manusia seutuhnya. Untuk ini pemahaman tentang
kepribadian pasien, maksud kunjungan pasien, kebutuhan kesehatan
pasien serta sikap dan perilaku pasien sangat dianjurkan.
d. Melakukan komunikasi interpersonal yang baik
Langkah keempat yaitu melakukan komunikasi interpersonal yang baik
terutama pada waktu kunjungan pertama pasien ke tempat praktek.
Banyak hal yang bisa dilakukan terutama melakukan wawancara
(anamnesis) dengan baik, dengan tujuan utama adalah membina
hubungan atas dasar kepercayaan (rapport).
e. Membina komunikasi yang terus-menerus dan berkesinam bungan
Membina komunikasi yang terus menerus dan berkesinambungan antara
dokter dengan pasien, misalnya dengan menghubungi pasien melalui
telepon atau mengunjungi rumah pasien. Tetapi dalam melakukan
komunikasi yang terus-menerus dan berkesinambungan jangan sampai
menimbulkan ketergantungan atau kunjungan pasien yang berlebihan.
F. PROSEDUR WAWANCARA
• Memberikan salam.
• Membuat suasana tenteram.
• Membina rapport.
• Mempunyai waktu.
• Bagian awal; terbuka (biarkan pasien bicara dengan kata-katanya sendiri)
patient centered.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 27
Buku Panduan CSL 1 2017
• Pertanyaan terbuka untuk menggali masalah pasien, pertanyaan
tertutup untuk klarifikasi masalah. Terlalu banyak pertanyaan tertutup
akan mengekang pasien.
• Mendengarkan dengan pengertian dan merasakan apa yang dikeluhkan
pasien (empati).
• Menstimulasi verbal pasien.
• Melakukan refleksi isi yang berarti mengungkapkan apa yang
disampaikan pembicara/pasien dengan kata-kata kita sendiri. Refleksi isi,
dilakukan untuk mengetahui apakah informasi yang kita terima memang
sesuai dengan yang dimaksud pembicara/pasien.
• Melakukan refleksi perasaan yaitu mengungkapkan perasaan/emosi
yang dirasakan pembicara/pasien. Refleksi perasaan dilakukan untuk
mengetahui dan memastikan emosi yang dirasakan pembicara/pasien.
• Refleksi isi dan perasaan biasanya dilakukan bersama-sama
Contoh:
“Dok, saya datang lagi, sebab keluar darah banyak. Waktu itu,saya
dipasang KB apa sih? Saya takut kalau-kalau bahaya, jadi saya cepat-
cepat kesini.”
Refleksi isi:
“Oh ibu datang kembali karena ada masalah perdarahan? Bisa ibu
ceritakan lebih jelas tentang perdarahan ini ?”
Refleksi perasaan:
“Aduh saya ikut prihatin dengan kejadian ini. Ibu merasa cemas dan
takut ya?”
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 28
Buku Panduan CSL 1 2017
• Merangkum menyusun informasi yang disampaikan oleh
pembicara/pasien dengan kata-kata kita sendiri. Merangkum dilakukan
setelah pembicara/pasien berbicara untuk jangka waktu tertentu.
Merangkum berarti mengambil intisari dari informasi yang kita terima.
Contoh:
“ jadi bapak/ibu sudah merasakan keluhan ini sejak 4 hari yang lalu dan
keluhan ini menetap meskipun bapak/ibu sudah minum obat warung,
selain itu juga ada beberapa keluhan penyerta yang membuat bapak/ibu
merasa tidak nyaman”
• Menggunakan pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang menghasilkan
jawaban yang menjelaskan apa yang dipikirkan pasien, membuat pasien
ikut bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan.
Contoh :
-Tolong jelaskan rasa sakit yang dirasakan bapak ?
-Informasi apa yang bapak inginkan ?
• Menggunakan pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang
menghasilkan jawaban pendek dan spesifik: ya , tidak, setuju, 38 tahun, 3
orang, dll.
Contoh :
- Ibu mau pakai pil KB ?
- Rasa sakitnya seperti ditusuk-tusuk ?
• Menggunakan pertanyaan mendalam merupakan lanjutan dari
pertanyaan terbuka yaitu untuk mengetahui lebih lanjut pernyataan
pasien.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 29
Buku Panduan CSL 1 2017
Contoh :
- Mengapa ibu mengatakan bahwa IUD itu kurang baik?
- Tolong jelaskan alasan bapak untuk tidak setuju melakukan olahraga
teratur
• Memberikan kesempatan pasien untuk bertanya
Contoh:
“bagaimana bapak/ibu apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, atau
apakah dari penjelasan saya ada yang kurang jelas?”
• Menutup komunikasi pada waktu yang tepat.
G. REFERENSI
1. Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Pusat penerbitan Depdiknas. Jakarta
2. Bickley L.S. BATES; Guide to Physical Examination and History Taking
(Ninth Edition), Lippincott Williams & Wilkins
3. Gan G.L. et all. 2004. A Primer On Family Medicine Practice, Singapore
International Foundation, Singapore.
4. Azwar A. 1996. Pengantar Pelayanan Dokter Keluarga.Yayasan
Penerbit IDI. Jakarta
5. Mc Whinney. 1989. A Text Book of Family Medicine. Oxford University.
New York
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 30
Buku Panduan CSL 1 2017
2. CHECK LIST KETRAMPILAN HUBUNGAN DOKTER PASIEN
N Skor Feed Back
Aspek
o 0 1 2
I INTERPERSONAL
1 Membina rapport (menyambut dengan
ramah, salam, menyilakan duduk, perkenalan
diri, sikap terbuka, kesejajaran)
2 Membuka pembicaraan ( meminta pasien
bicara terbuka, utk kepentingan pasien,
prinsip kerahasiaan, sehingga dapat
memercayai dokter)
3 Wajah ramah, senyum, posisi tubuh baik,
kontak mata selama interaksi
II CONTENT
4 Banyak menggunakan pertanyaan terbuka
dalam mengeksplorasi permasalahan pasien
5 Menggunakan pertanyaan tertutup yang
sesuai
6 Mengajukan pertanyaan yang mendalam jika
diperlukan
7 Melakukan refleksi isi
8 Melakukan refleksi perasaan
9 Memberikan informasi yang benar
10 Memberikan informasi dengan bahasa
sederhana yang dipahami pasien
11 Memberikan informasi yang lengkap
12 Memberikan kesempatan pasien untuk
bertanya
13 Memegang kendali selama komunikasi
14 Menutup komunikasi pada waktu yang tepat
III PROFESSIONALISM
15 Melakukan dengan penuh percaya diri
16 Melakukan dengan kesediaan membantu &
empati
17 Melakukan dengan kesalahan minimal
TOTAL
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 31
Buku Panduan CSL 1 2017
Nilai = ------------- x 100% = …………
..: CUCI TANGAN STANDAR WHO
dr. Dian Isti Angraini | dr. Hanna Mutiara
A. TEMA
Cuci tangan standar WHO
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur mencuci tangan
yang sesuai dengan standar WHO sebelum semua tindakan
C. ALAT DAN BAHAN
• Kran air
• Sabun cuci tangan atau alkohol 70%
• Lap tangan atau handuk kecil
D. SKENARIO
Seorang pria berusia 47 tahun datang ke klinik anda dengan keluhan luka
pada kakinya dan berbau. Diketahui dari hasil anamnesis dan pemeriksaan
laboratorium bahwa pasien tersebut mengidap diabetes. Sebelum
melakukan tindakan medis pada luka tersebut anda sebagai dokter yang
profesional melakukan cuci tangan WHO terlebih dahulu.
E. DASAR TEORI
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 32
Buku Panduan CSL 1 2017
Mencuci tangan merupakan hal sederhana yang penting untuk dilakukan
namun seringkali diabaikan. Sebenarnya, mencuci tangan merupakan
suatu keharusan untuk melindungi kita dari bahaya kuman. Banyak kuman
yang dapat ditularkan melalui tangan dan menyebabkan kita menjadi sakit,
misalnya droplet (percikan ludah) pada saat batuk atau bersin, benda-
benda yang telah terkontaminasi oleh kuman, cairan tubuh penderita
(misalnya keringat, air seni, darah). Mencuci tangan yang baik merupakan
benteng pertahanan tubuh pertama dalam mencegah kita sakit ataupun
menularkan kuman pada orang lain.
Kapan sebaiknya mencuci tangan?
Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum menyiapkan makanan,
sebelum dan setelah makan, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit,
sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin atau
membuang ingus, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan
setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah,
setelah menyentuh hewan atau kotoran hewan.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 33
Buku Panduan CSL 1 2017
F. PROSEDUR KETERAMPILAN MENCUCI TANGAN
1. Pastikan kuku jari tangan tidak panjang
2. Lepaskan semua perhiasan yang ada (cincin, gelang, jam tangan)
3. Singsingkan lengan baju jika Anda menggunakan baju berlengan
panjang
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 34
Buku Panduan CSL 1 2017
4. Putar kran air pada posisi ‘on’ sehingga air mengalir
5. Basahi tangan sampai dengan pergelangan tangan
6. Ambil sabun cuci tangan (sebaiknya mengandung antiseptik) atau
alkohol 70% (jika menggunakan alkohol 70% tidak melakukan poin 3
dan 4)
7. Lakukan metode cuci tangan 6 langkah (dengan air mengalir jika
menggunakan sabun cuci tangan dan air):
a) Telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri
b) Telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan telapak
tangan kiri di atas punggung tangan kanan
c) Telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri dengan jari saling
terkait
d) Punggung jari tangan kanan pada telapak tangan kiri dengan jari
saling mengunci dan sebaliknya
e) Ibu jari tangan kanan digosok memutar dengan telapak tangan kiri
dan sebaliknya
f) Jari-jari tangan kanan menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke
kiri pada telapak tangan kiri dan sebaliknya
Sumber: WHO
8. Mengeringkan tangan dengan tisue, lap atau handuk bersih
9. Memutar kran air pada posisi ‘off’ dengan menggunakan tisue
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 35
Buku Panduan CSL 1 2017
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 36
Buku Panduan CSL 1 2017
G. REFERENSI
1. Azwar Azrul. 1996. Pengantar Pelayanan Dokter Keluarga.Yayasan
Penerbit IDI. Jakarta
2. Bickley, Lynn. S, BATES; Guide to Physical Examination and History
Taking (Ninth Edition), Lippincott Williams & Wilkins
3. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia..
Pusat penerbitan Depdiknas. Jakarta
4. Gan, Goh Lee, at all. 2004. A Primer On Family Medicine Practice,
Singapore International Foundation, Singapore.
5. Mc Whinney. 1989A Text Book of Family Medicine.Oxford University.
New York
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 37
Buku Panduan CSL 1 2017
3. CHECKLIST LATIHAN CUCI TANGAN WHO
Skor Feed Back
No Aspek
0 1 2
INTERPERSONAL
1 Membina rapport (menyambut
dengan ramah, salam, menyilakan
duduk, perkenalan diri, sikap terbuka,
kesejajaran)
2 Informed consent
CONTENT
3 Pastikan kuku jari tangan tidak
panjang, Lepaskan semua perhiasan
yang ada (cincin, gelang, jam tangan)
4 10. Singsingkan lengan baju jika Anda
menggunakan baju berlengan
panjang
5 1. Putar kran air pada posisi ‘on’
sehingga air mengalir
6 1. Basahi tangan sampai dengan
pergelangan tangan
7 1. Ambil sabun cuci tangan (sebaiknya
mengandung antiseptik) atau
alkohol 70% (jika menggunakan
alkohol 70% tidak melakukan poin 3
dan 4)
8 11. Lakukan metode cuci tangan 6
langkah (dibawah air mengalir jika
menggunakan sabun cuci tangan dan
air):
g) Telapak tangan kanan dengan
telapak tangan kiri
h) Telapak tangan kanan di atas
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 38
Buku Panduan CSL 1 2017
punggung tangan kiri dan telapak
tangan kiri di atas punggung tangan
kanan
i) Telapak tangan kanan dan telapak
tangan kiri dengan jari saling terkait
j) Punggung jari tangan kanan pada
telapak tangan kiri dengan jari saling
mengunci dan sebaliknya
k) Ibu jari tangan kanan digosok
memutar dengan telapak tangan kiri
dan sebaliknya
l) Jari-jari tangan kanan menguncup,
gosok memutar ke kanan dan ke kiri
pada telapak tangan kiri dan
sebaliknya
Sumber: WHO
9 1. Mengeringkan tangan dengan tisue,
lap atau handuk bersih
101. Memutar kran air pada posisi ‘off’
dengan menggunakan tisue
PROFESSIONALISM
11 Melakukan dengan penuh percaya
diri
12 Melakukan dengan kesalahan
minimal
TOTAL
Nilai = ------------- x 100% = ……………
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 39
Buku Panduan CSL 1 2017
..: GENERAL SURVEY
dr. Hanna Mutiara
A. TEMA
Keterampilan Klinis Pemeriksaan Fisik General Survey
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah melalui CSL ini diharapkan mahasiswa mampu untuk:
1. melakukan persiapan sebelum pemeriksaan.
2. melakukan pengamatan langsung terhadap pasien secara umum dan
keseluruhan.
3. melakukan pemeriksaan BMI.
4. menyimpulkan status sehat/sakit pasien secara umum.
C. ALAT DAN BAHAN
• Bed periksa pasien.
• Meja dan kursi periksa.
• Alkohol 70% atau set cuci tangan + lap.
• Stetoskop.
• Kapas alkohol.
• Microtoise.
• Timbangan Berat Badan.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 40
Buku Panduan CSL 1 2017
D. SKENARIO
Anda adalah dokter di Puskesmas Sukagalau, siang itu datang pasien laki-
laki gemuk berusia 35 tahun diantar oleh keluarganya dengan keluhan
cepat lelah. Pasien tampak berkeringat banyak, nafas cepat, berpenampilan
bersih, berpakaian kaos dan celana pendek, berkulit sawo matang namun
terdapat banyak garis-garis kehitaman di belakang lehernya. Lakukanlah
pengamatan dan pemeriksaan selanjutnya!
E. DASAR TEORI
General Survey adalah melakukan observasi/pengamatan terhadap
keseluruhan status kesehatan pasien secara umum. Hal tersebut dapat
mencakup tinggi badan, berat badan, pertumbuhan dan perkembangan
seksual, postur tubuh, cara berjalan, personal hygyene, aroma tubuh dan
nafas, ekspresi wajah, reaksi terhadap lingkungan, cara berbicara dan
tingkat kesadaran.
Pengamatan tersebut dapat langsung dilakukan sejak permulaan
berhadapan dengan pasien. Seorang klinisi yang baik akan melatih
kemampuan mereka dalam melakukan pengamatan tersebut secara
berkesinambungan sehingga keahlian tersebut semakin terasah. Hal ini
penting untuk meningkatkan ketajaman dan sensitivitas seorang dokter
dalam menilai pengetahuan, sikap dan perilaku pasien sehingga dapat
menemukan perbedaan yang khas dari setiap keadaan pasien.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 41
Buku Panduan CSL 1 2017
Banyak faktor yang berperan terhadap keadaan pasien, seperti status
ekonomi, nutrisi, keturunan, pengetahuan, penyakit terdahulu, jenis
kelamin, lokasi geografis, dan usia. Latar belakang pasien tersebut
berpengaruh terhadap status gizi: berat dan tinggi badan, tekanan darah,
postur, mood, kewaspadaan/kesadaran, keadaan rongga mulut, warna
kuku, penampakan otot tubuh dll. Pastikanlah Anda melakukan penilaian
terhadap berat badan, tinggi badan, BMI, dan resiko obesitas setiap
berhadapan dengan pasien.
Kini latihlah diri anda untuk melakukan pengamatan terhadap pasien anda
sejak pertama kali anda berinteraksi. Perhatikan bagaimana kesan pasien
ketika anda menyambutnya? Perhatikan apakah pasien berjalan dengan
mudah atau kaku? Apakah pasien dapat naik ke bed pemeriksaan dengan
mudah? Atau jika pasien menjalani perawatan inap di RS, amati pada saat
anda melakukan visite. Apakah pasien terbaring lemah? atau duduk dan
menonton tv? Perhatikan apa yang ada di sebelahnya apakah majalah?
atau kitab suci? lihat apakah pasien dipasangi alat bantu seperti kateter
urin? dan sebagainya. Hal-hal yang anda amati tersebut dapat membantu
anda dalam membuat hipotesis tentang keadaan kesehatan pasien dan
mungkin prognosisnya.
Dalam melakukan general survey, perhatikanlah:
Keadaan umum Kesan sehat/sakit. Cobalah untuk membuat
kesimpulan umum berdasar pengamatan anda selama berinteraksi
dengan pasien. Keadaan umum dapat terbagi atas kesan sehat, kesan
sakit ringan (misalnya pasien masih dapat berjalan, tersenyum,
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 42
Buku Panduan CSL 1 2017
memperhatikan penampilan), kesan sakit sedang (pasien tampak agak
lemah, terganggu dengan keadaan sakitnya, sedikit meringgis) dan
kesan sakit berat (pasien tampak lemah, tidak dapat melakukan
aktivitas sehari-hari sendiri (membersihkan diri, menggunakan pakaian,
makan dan minum) dll
Tingkat kesadaran Kesadaran adalah produk neurofisiologik dimana
seorang individu mampu berorientasi secara wajar terhadap diri
sendiri dan lingkungan. Sedangkan definisi yang lain yaitu keadaan
yang mencerminkan pengintegrasian rangsang aferen dan eferen.
Penilaian tingkat kesadaran dapat dilakukan secara kualitatif maupun
kuantitatif. Tingkat kesadaran kualitatif antara lain:
Compos mentis Keadaan sistem sensorik utuh, ada waktu tidur dan
sadar penuh serta aktivitas yang teratur.
Somnolen Keadaan mengantuk dan dapat disebut juga sebagai
letargi. Dapat bangun spontan pada waktunya atau
sesudah dirangsang dengan ringan, tapi kembali tidur
setelah stimulasi dihilangkan. Pasien mampu memberi
jawaban verbal dan menangkis rangsang nyeri.
Stupor Kantuk yang dalam. Pasien terlihat tertidur tapi dapat
dibangunkan dengan rangsang verbal yang kuat, dapat
spontan hanya waktu singkat, sistem sensorik berkabut,
dapat mengikuti beberapa perintah sederhana. Tidak
dapat diperoleh jawaban verbal dari pasien. Gerak
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 43
Buku Panduan CSL 1 2017
motorik untuk menangkis rangsang nyeri masih baik.
Semikoma/ Pasien tidak ada respon dengan rangsang verbal,
soporokomatus dengan rangsang nyeri masih ada gerakan, reflek‐reflek
(cornea, pupil dll) masih baik dan nafas masih adekuat.
Koma Koma adalah suatu keadaan tidak sadar total terhadap
diri sendiri dan lingkungan meskipun distimulasi dengan
kuat. Gerakan spontan negatif, reflek‐reflek negatif,
fungsi nafas terganggu atau negatif. Tidak ada respon
sama sekali terhadap rangsang nyeri yang
bagaimanapun kuatnya.
Sedangkan penilaian kesadaran kuantitatif menggunakan suatu
patokan yang disebut Glasgow Coma Scale (GCS)
Tanda–tanda stress misalnya: apakah pasien menunjukkan gejala
cadiac atau respiratory distress? nyeri? Ansietas/cemas berlebihan?
atau depresi?
Tinggi dan bentuk tubuh mintalah pasien untuk membuka alas
kakinya dan lakukanlah pengukuran tinggi badan. Simpulkan apakah
pasien tinggi atau pendek? Bentuk tubuh kurus, ramping atau pendek
gemuk? tegap atau tidak? simetris atau tidak? perhatikan apakah
pasien terlhat proporsional? perhatikan pula jika terdapat deformitas.
Berat badan perhatikan apakah pasien kurus kering, gemuk,
obesitas, atau mungkin di antaranya? Jika pasien gemuk, perhatikan
apakah penyebaran lemaknya merata atau berpusat pada tungkai,
badan bagian atas, atau sekeliling pinggul?
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 44
Buku Panduan CSL 1 2017
Warna kulit dan lesi yang mungkin ada, atau bahkan terdapat
pembuluh darah yang melebar
Pakaian dan personal higiene perhatikan bagaimana penampilan
pasien. Apakah pasien menggunakan pakaian yang sesuai dengan
cuaca? apakah bersih? berkancing atau beresleting? apakah sesuai
dengan usia dan nilai sosial? Lalu perhatikan alas kaki pasien apakah
menggunakan sepatu? sandal? sepatu olah raga? atau bahkan tanpa
alas kaki? Apakah pasien menggunakan perhiasan? cara menggunakan
perhiasan yang wajar? atau tindik (body piercing)? Perhatikan pula
rambut pasien, kuku jari, serta penggunaan kosmetik. Hal-hal tersebut
dapat menjadi petunjuk kepribadian pasien, mood dan gaya hidupnya.
Ekspresi wajah perhatikan ekspresi wajah pasien saat diam, saat
berbicara, pemeriksaan fisik dan ketika berinteraksi dengan orang lain.
Amati kontak matanya, apakah natural? Terpaku tidak berkedip? atau
bergerak cepat?
Aroma tubuh dan nafas Bau-bauan merupakan petunjuk yang
penting, misalnya bau keton pada pasien diabetes, atau bau alkohol.
Postur, cara berjalan dan aktivitas motorik perhatikan postur
pasien, apakah pasien gelisah atau diam? berapa kali pasien merubah
posisinya? berapa cepat pergerakannya? apakah terdapat pergerakan
yang tidak disadari? apakah ada bagian tubuh yang tidak dapat
digerakkan? bagaimana cara berjalan pasien? perlahan-lahan, tampak
nyaman dan percaya diri, seimbang, atau terlihat kekakuan dari
tungkai, seperti mau jatuh, tidak seimbang, atau gangguan lainnya?
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 45
Buku Panduan CSL 1 2017
F. PROSEDUR
1. Sambung rasa sambil memulai melakukan general survey
2. Amati dan perhatikan
Keadaan umum kesan sehat, sakit ringan, sedang, berat.
Tingkat kesadaran komposmentis, somnolen, stupor,
soporokomatus, atau koma. Cobalah memberi beberapa
pertanyaan kepada pasien atau beri rangsang nyeri dan beri
penilaian.
Bentuk tubuh Bentuk tubuh kurus, ramping atau pendek
gemuk? tegap atau bungkuk? simetris atau tidak? perhatikan
apakah pasien terlihat proporsional? perhatikan pula jika terdapat
deformitas.
Warna kulit dan lesi yang mungkin ada, atau bahkan terdapat
pembuluh darah yang melebar
Pakaian dan personal higiene perhatikan bagaimana
penampilan pasien. Cara berpakaian, jenis pakaian
berkancing/resleting atau tidak, kebersihan, sesuai dengan usia
dan nilai sosial, alas kaki yang pasien gunakan, perhiasan yang
digunakan, cara menggunakan perhiasan tersebut, rambut pasien,
kuku jari, serta penggunaan kosmetik.
Ekspresi wajah perhatikan ekspresi wajah pasien saat diam,
saat berbicara, saat pemeriksaan fisik dan ketika berinteraksi
dengan orang lain. Amati pula kontak matanya.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 46
Buku Panduan CSL 1 2017
Aroma tubuh dan nafas Bau-bauan merupakan petunjuk yang
penting, misalnya bau keton pada pasien diabetes, atau bau
alkohol.
Postur, cara berjalan dan aktivitas motorik perhatikan postur
pasien, apakah pasien gelisah atau tidak? berapa kali pasien
merubah posisinya? berapa cepat pergerakannya? apakah
terdapat pergerakan yang tidak disadari? apakah ada bagian tubuh
yang tidak dapat digerakkan? bagaimana cara berjalan pasien?
3. Cuci tangan WHO sebelum memeriksa pasien
4. Lakukan pengukuran tinggi badan
Minta pasien untuk melepaskan alas kaki.
Atur posisi pasien sehingga berdiri tegak lurus di bawah microtoise
membelakangi dinding dengan kepala tegak dan pandangan lurus
ke depan. Pastikan pasien berdiri tegak, kedua lutut dan tumit
rapat, kaki lurus, tumit, pantat, punggung, dan kepala bagian
belakang harus menempel pada dinding. Untuk pasien obesitas
dimana posisi tersebut sulit dilakukan, maka tidak perlu keempat
titk tersebut menempel pada dinding, asalkan tulang belakang dan
pinggang dalam seimbang (tidak membungkuk atau tengadah).
Tarik kepala microtoise sampai puncak kepala pasien.
Baca angka pada jendela baca dan mata pembaca harus sejajar
dengan garis merah.
Angka yang dibaca adalah yang berada pada garis merah dari
angka kecil ke angka besar.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 47
Buku Panduan CSL 1 2017
Baca angka pada skala yang nampak pada lubang dalam gulungan
mikrotoa. Angka tersebut menunjukkan tinggi pasien yang diukur.
Lanjutkan dengan menimbang berat badan pasien
5. Lakukan pengukuran berat badan
Pastikan timbangan badan berfungsi baik dan stel penunjuk pada
titik nol
Pastikan tidak ada beban tambahan ditubuh pasien yang
mempengaruhi penimbangan, dengan cara meminta pasien
melepas semua jaket, tas, perhiasan, atau barang lainnya.
Bimbing pasien untuk naik ke atas timbangan dan diam ditempat
sambil kita melihat angka yang ditunjukkan oleh jarum pengukur
tempat penunjuk berhenti
Catat hasil pengukuran.
Persilahkan pasien untuk turun dengan perlahan dari timbangan
6. Hitunglah BMI (Body Mass Index) pasien dengan menggunakan rumus:
Berat badan (kg)
Tinggi(m)2
Hasil penghitungan IMT dibulatkan satu desimal
WHO menyatakan bahwa batasan berat badan normal orang dewasa
ditentukan berdasarkan nilai body mass index (BMI) atau indeks Masa
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 48
Buku Panduan CSL 1 2017
Tubuh (IMT). Body Mass Index efektif digunakan sebagai alat untuk
mensekrening kondisi atau status gizi seseorang khususnya yang
berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, tetapi bukan
sebagai suatu alat diagnostik.
Penilaian hasil penghitungan Body Mass Index berdasarkan WHO
populasi Asia disajikan pada tabel berikut :
Status Gizi IMT
Kurang <18.5
Normal 18.5 - <23
Overweight 23 - <25
Obesitas 25 - <27
Derajat I
Obesitas ≥27
Derajat II
Seorang dikatakan kurus bila IMT nya < 18.5 dan gemuk bila IMT nya >
23. Bila IMT >25 orang tersebut menderita obesitas dan perlu
diwaspadai karena biasanya orang tesebut juga menderita penyakit
degeneratif seperti Diabetes Melitus, hipertensi, hiperkolesterol dan
kelainan metabolisme lain yang memerlukan pemeriksaan lanjut baik
klinis atau laboratorium
7. Cuci tangan WHO setelah memeriksa pasien.
8. Tutup interaksi dengan pasien.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 49
Buku Panduan CSL 1 2017
G. DAFTAR PUSTAKA
Bate’s barbara. 2007. Guide to physical examination. Lippincot.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 50
Buku Panduan CSL 1 2017
4. CHECK LIST LATIHAN KETERAMPILAN PEMERIKSAAN GENERAL SURVEY
Skor Feed Back
No Aspek
0 1 2
I INTERPERSONAL
1 Sambung Rasa (Membina rapport / menyambut
dengan ramah, salam, menyilakan duduk,
perkenalan diri, komunikasi non verbal)
2 Informed consent untuk pengukuran tinggi dan
berat badan
II CONTENT
3 Amati dan perhatikan (nilai pada poin 16)
• Keadaan umum
(kesan sehat, sakit ringan, sedang, berat)
• Tingkat kesadaran
(komposmentis, somnolen, stupor,
soporokomatus, atau koma)
• Bentuk tubuh
(Bentuk tubuh kurus, ramping atau pendek
gemuk? tegap atau bungkuk? simetris?
Proporsional? Deformitas?)
• Warna kulit dan lesi
• Pakaian dan personal higiene
(Cara berpakaian, jenis pakaian
berkancing/resleting atau tidak, kebersihan,
sesuai dengan usia dan nilai sosial, alas kaki
yang pasien gunakan, perhiasan yang
digunakan, cara menggunakan perhiasan
tersebut, rambut pasien, kuku jari, serta
penggunaan kosmetik)
• Ekspresi wajah
(perhatikan ekspresi wajah pasien saat
diam, saat berbicara, saat pemeriksaan fisik
dan ketika berinteraksi dengan orang lain.
Amati pula kontak matanya)
• Aroma tubuh dan nafas
• Postur, cara berjalan dan aktivitas motorik
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 51
Buku Panduan CSL 1 2017
(perhatikan postur pasien, cara berjalan,
cara duduk, apakah pasien gelisah atau
tidak? berapa kali pasien merubah
posisinya? berapa cepat pergerakannya?
apakah terdapat pergerakan yang tidak
disadari? apakah ada bagian tubuh yang
tidak dapat digerakkan? Lainnya)
4 Cuci tangan WHO
Lakukan pengukuran tinggi badan
5 Minta pasien untuk melepaskan alas kaki
6 Atur posisi pasien sehingga berdiri tegak lurus
di bawah microtoise membelakangi dinding
dengan kepala tegak dan pandangan lurus ke
depan. Pastikan pasien berdiri tegak, kedua
lutut dan tumit rapat, kaki lurus, tumit, pantat,
punggung, dan kepala bagian belakang harus
menempel pada dinding.
7 Tarik kepala microtoise sampai puncak kepala
pasien
8 Baca angka pada jendela baca dan mata
pembaca harus sejajar dengan garis merah.
9 Catat hasil pengukuran
Lakukan pengukuran berat badan
10 Pastikan timbangan badan berfungsi baik dan
setel penunjuk pada titik nol.
11 Pastikan tidak ada beban tambahan ditubuh
pasien yang mempengaruhi penimbangan,
dengan cara meminta pasien melepas jaket,
tas, perhiasan, atau barang lainnya.
12 Bimbing pasien untuk naik ke atas timbangan
(tengah) dan diam ditempat sambil kita melihat
angka yang ditunjukkan oleh jarum pengukur
tempat penunjuk berhenti (mata vertikal!)
13 Catat hasil pengukuran
14 Persilahkan pasien untuk turun dengan
perlahan dari timbangan
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 52
Buku Panduan CSL 1 2017
15 Cuci tangan WHO
16 Hitunglah BMI (Body Mass Index) pasien
17 Tutup interaksi dengan pasien.
18 Laporkan hasil pengamatan general survey:
• Keadaan umum
• Tingkat kesadaran
• Bentuk tubuh
• Warna kulit dan lesi
• Pakaian dan personal higiene
• Ekspresi wajah
• Aroma tubuh dan nafas
• Postur, cara berjalan dan aktivitas motorik
• Tinggi badan dan Berat badan
• BMI
III PROFESIONALISM
19 Melakukan dengan percaya diri
20 Melakukan dengan kesalahan minimal
TOTAL
Nilai = ------------- x 100% = ……………
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 53
Buku Panduan CSL 1 2017
..: PEMERIKSAAN VITAL SIGN
dr. Hanna Mutiara | dr. Novita C., MSc | dr. Dian I. Angraini, MPH
A. TEMA
Pemeriksaan vital sign: suhu, tekanan darah, nadi, nafas
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah melalui CSL ini diharapkan mahasiswa mampu untuk:
Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (vital sign) meliputi pemeriksaan
tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi rate (frekuensi pernafasan) dengan
menggunakan alat yang sesuai secara baik dan benar.
C. ALAT DAN BAHAN
• Alkohol 70% atau set cuci tangan (sabun pencuci tangan + Lap tangan).
• Sphygmomanometer (raksa dan atau aneroid).
• Stetoskop.
• Termometer.
• Stopwatch.
• Kapas dan alkohol.
D. SKENARIO
Anda adalah seorang dokter jaga pada Klinik 24 jam. Lalu datanglah Tn. Adi,
30 tahun, dengan keluhan pusing berputar sudah 3 hari. Keluhan disertai
dengan mual, muntah dan badan lemas sejak 1 hari. Setelah melakukan
anamnesis, Anda melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 54
Buku Panduan CSL 1 2017
tersebut. Lakukanlah!
E. DASAR TEORI
1. Pemeriksaan Tekanan Darah
Dalam melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, lakukanlah
pemeriksaan tekanan darah atau pulsasi nadi terlebih dahulu. Jika
terdapat tekanan darah yang tinggi, lakukanlah pemeriksaan ulang
tekanan darah setelah melakukan pemeriksaan yang lain.
Tekanan darah pada sistem arteri bervariasi sesuai dengan siklus
jantung, yaitu memuncak pada waktu sistole dan sedikit menurun pada
waktu diastole. Beda antara tekanan sistole dan diastole disebut
tekanan nadi. Pada waktu ventrikel berkontraksi, darah akan
dipompakan ke seluruh tubuh, keadaan ini disebut keadaan sistole,
dan tekanan aliran darah pada saat itu disebut tekanan darah sistole.
Pada saat ventrikel sedang rileks, darah dari atrium masuk ke ventrikel,
tekanan aliran darah pada waktu ventrikel sedang rileks tersebut
disebut tekanan darah diastole. Tingginya tekanan darah
dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya aktivitas fisik, keadaan
emosi, rasa sakit, suhu sekitar, penggunaan kopi, tembakau, dll.
Sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah, pilihlah dahulu
ukuran cuff (manset) yang sesuai untuk pasien. Manset yang terlalu
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 55
Buku Panduan CSL 1 2017
kecil (sempit) dapat menyebabkan interpretasi peningkatan tekanan
darah yang salah dalam pemeriksaan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih cuff (manset)
yang tepat adalah:
• Lebar manset sebaiknya meliputi 40% dari keliling lengan atas
(umumnya 12-14 cm pada manset orang dewasa).
• Panjang manset yang dapat digembungkan (bladder) sebaiknya
80% dari lingkar lengan atas (cukup panjang untuk mengelilingi
lengan atas).
• Jika Anaeroid, sebaiknya lakukan kalibrasi ulang secara periodik.
Gambar. Sphygmomanometer air raksa dan aneroid
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan
pemeriksaan tekanan darah adalah:
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 56
Buku Panduan CSL 1 2017
• Idealnya, minta pasien Anda untuk tidak merokok atau meminum
minuman berkafein 30 menit sebelum pemeriksaan.
• Minta pasien anda untuk beristirahat 5 menit sebelum
pemeriksaan.
• Lakukan pemeriksaan pada ruang pemeriksaan yang sunyi dan
nyaman.
• Pastikan lengan yang akan dilakukan pemeriksaan terbebas dari
pakaian, tidak ada fistula, scar atau tanda lymphedema.
• Palpasi arteri brachial untuk memastikan terdapat pulsasi nadi
• Posisikan lengan pasien sedemikian rupa sehingga arteri brachial
(pada sudut antecubital) sejajar dengan tinggi jantung atau pada
interspace/intercosta ke 4.
Gambar. Posisi lengan dalam pengukuran tekanan darah
• Jika pasien dalam posisi duduk, sanggalah lengan pasien oleh meja
pemeriksaan, diatas pinggang pasien.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 57
Buku Panduan CSL 1 2017
• Jika pasien dalam keadaan berdiri, usahakan menyangga lengan
pasien pada pertengahan dada.
2. Pemeriksaan Nadi
Melalui pemeriksaan nadi, kita dapat menghitung denyut jantung,
menentukan irama amplitudo, gelombang pulsasi dan terkadang
mendeteksi obstruksi aliran darah. Pulsasi radialis umumnya dapat
digunakan untuk menilai denyut jantung. Ketika iramanya irregular
maka lakukan evaluasi dengan mendengarkan bunyi jantung
(auskultasi menggunakan stetoskop).
Jantung bekerja memompa darah ke sirkulasi tubuh (oleh ventrikel kiri)
dan paru (oleh ventrikel kanan). Melalui ventrikel kiri, disemburkan
darah ke aorta dan kemudian diteruskan ke arteri di seluruh tubuh.
Sebagai akibatnya, timbullah suatu gelombang tekanan yang bergerak
cepat pada arteri dan dapat dirasakan sebagai denyut nadi. Dengan
menghitung frekuensi denyut nadi, dapat diketahui frekuensi jantung
dalam satu menit.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 58
Buku Panduan CSL 1 2017
Gambar. Pemeriksaan denyut nadi
3. Pemeriksaan Pernafasan
Bernafas adalah suatu tindakan yang tidak disadari, diatur oleh batang
otak dan dilakukan dengan bantuan otot-otot pernafasan. Pada waktu
inspirasi, diafragma dan otot-otot interkostalis berkontraksi,
memperluas rongga toraks dan memekarkan paru –paru. Dinding dada
akan bergerak ke atas, ke depan, dan ke lateral, sedangkan diafragma
bergerak ke bawah. Setelah inspirasi berhenti, paru-paru akan
mengkerut, diafragma akan naik secara pasif dan dinding dada akan
kembali ke posisi semula.
Dalam melakukan pemeriksaan pernafasan, observasilah frekuensi,
irama, kedalaman dan usaha bernafas (effort of breathing). Hitunglah
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 59
Buku Panduan CSL 1 2017
frekuensi pernafasan dalam 1 menit melalui inspeksi atau
mendengarkan menggunakan stetoskop. Normalnya frekuensi
pernafasan pada orang dewasa adalah 14-20 kali/menit dengan irama
yang reguler.
Gambar. Pemeriksaan Pernafasan
4. Pemeriksaan Suhu
Suhu badan diperiksa dengan termometer badan, dapat berupa
termometer air raksa atau termometer elektrik/digital. Pemeriksaan
dapat dilakukan pada mulut, aksila atau rektum. Pengukuran suhu
melalui mulut biasanya lebih mudah dan hasilnya lebih tepat
dibandingkan melalui rektum. Rata-rata suhu tubuh yang dilakukan
pengukuran melalui mulut adalah 370C (98.60F). Pemeriksaan secara
rektum biasanya memberikan hasil pemeriksaan yang lebih tinggi
sebesar 0,4 – 0,5 derajat dibandingkan lewat mulut. Suhu aksila lebih
rendah 10C dari suhu mulut. Banyak pasien memilih pengukuran suhu
mulut dibandingkan rektal, namum hal ini tidak seyogyanya dipakai
pada penderita yang tidak sadar, gelisah, atau tidak dapat menutup
mulutnya (terutama jika menggunakan termometer air raksa dengan
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 60
Buku Panduan CSL 1 2017
kaca untuk menghindari termometer pecah karena pergerakan tiba-
tiba rahang pasien).
Gambar. Jenis-jenis termometer
F. PROSEDUR PEMERIKSAAN
1. Prosedur pemeriksaan tekanan darah:
a. Siapkan alat yang diperlukan (tensimeter dan stetoskop)
b. Siapkan pasien dapat dalam keadaan duduk atau berbaring
c. Lengan dalam keadaan bebas dan relaks, bebaskan dari tekanan
oleh karena pakaian.
d. Cuci tangan WHO sebelum melakukan pemeriksaan.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 61
Buku Panduan CSL 1 2017
e. Letakkan manset pada lengan atas sedemikian rupa sehingga
pusat dari manset yang dapat digembungkan (bladder) berada
tepat di atas arteri brachialis (biasanya terletak disebelah medial
tendo biseps)
f. Ujung bawah manset berjarak 2,5 cm di atas sudut antecubital.
g. Lingkarkan manset pada lengan atas pasien secara pas (tidak
longgar dan juga tidak terlalu ketat).
h. Posisikan lengan pasien sedikit fleksi(menekuk) pada siku
Gambar. Posisi lengan sedikit menekuk pada siku
i. Untuk menentukan seberapa tinggi Anda akan memberikan
tekanan pada manset, tentukanlah perkiraan tekanan systole
dengan cara palpasi terlebih dahulu. Letakkan jari Anda diatas
arteri brachialis atau arteri radialis pasien, naikkan tekanan
manset sampai pulsasi nadi arteri tersebut hilang, lihat tekanan
pada manometer dan tambahkan 30 mmHg.
j. Turunkan tekanan manset perlahan-lahan sampai denyutan a.
Brachialis teraba kembali. Inilah tekanan sistolik palpatoar.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 62
Buku Panduan CSL 1 2017
k. Kempiskan manset dengan segera dan tunggu 15 sampai 30 detik.
l. Ambil stetoskop dan letakkan diafragma stetoskop di atas arteri
brachialis.
m. Naikkan tekanan manset sampai tekanan yang telah ditentukan
tadi (kurang lebih 30 mm Hg di atas tekanan sistolik palpatoar).
n. Turunkan tekanan manset perlahan-lahan (2-3 mmHg/detik).
Perhatikan saat dimana denyutan arteri brachialis terdengar ini
adalah tekanan systole.
o. Turunkan terus tekanan manset sampai suara tersebut melemah
kemudian menghilang ini adalah tekanan diastole.
p. Kempiskan manset sampai tekanan pada manometer
menunjukkan skala nol.
q. Apabila menggunakan tensimeter air raksa, usahakan agar posisi
manometer selalu vertikal, dan pada waktu membaca hasilnya,
mata harus berada segaris horizontal dengan level air raksa.
r. Penggulangan pengukuran dilakukan setelah menunggu beberapa
menit setelah pengukuran pertama.
s. Lakukan pengukuran pada lengan sebelahnya. Adakah perbedaan
hasil pengukuran? (misalnya pada keadaan lansia dan obesitas).
2. Prosedur pemeriksaan nadi:
a. Siapkan pasien dapat dalam posisi duduk ataupun berbaring,
lengan pasien dalam posisi bebas (relaks), perhiasan dan jam
tangan dilepas.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 63
Buku Panduan CSL 1 2017
b. Periksalah denyut nadi pergelangan tangan pasien dengan
menggunakan jari telunjuk dan jari tengah anda, pada sisi fleksor
bagian lateral dari tangan penderita.
c. Raba dan beri sedikit tekanan di atas arteri radialis sehigga pulsasi
(denyutan) maksimal dapat dirasakan.
d. Perhatikan irama dan kuantitas denyutannya.
e. Jika iramanya reguler dan terasa normal, hitunglah jumlah
denyutan (frekuensi) selama 15 detik dan untuk mendapatkan
jumlah denyutan dalam satu menit kalikanlah 4 (empat). Jika
iramanya cepat atau lambat, hitunglah selama 60 detik. Jika
iramanya irreguler, lakukanla evaluasi dengan auskultasi jantung.
f. Bandingkan hasil pemeriksaan dari lengan kanan dan kiri.
3. Prosedur pemeriksaan pernafasan:
a. Minta pasien untuk melepaskan pakaian sehingga pergerakan
dinding dada dapat jelas terlihat.
b. Secara inspeksi, perhatikan secara menyeluruh gerakan
pernafasan (lakukan ini tanpa mempengaruhi psikis pasien).
c. Terkadang diperlukan cara palpasi, untuk sekalian mendapatkan
perbandingan antara kanan dan kiri.
d. Pada inspirasi, perhatikanlah: masuknya kembali iga, pelebaran
sudut epigastrium dan penambahan besarnya ukuran antero-
posterior dada.
e. Perhatikan pula apakah ada penggunaan otot bantu pernafasan.
f. Catatlah frekuensi, irama, dan ada tidaknya kelainan gerakan.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 64
Buku Panduan CSL 1 2017
4. Prosedur pemeriksaan suhu:
Pemeriksaan Pada Mulut (oral):
a. Jika menggunakan termometer air raksa, kibaskan termometer sampai
permukaan air raksa di bawah 35°C (960F)
b. Tempatkan termometer dibawah lidah penderita.
c. Mintalah penderita untuk menutup mulut, dan tunggu sampai 3 – 5
menit.
d. Kemudian bacalah termometer tersebut, pasangkan lagi selama satu
menit, dan baca kembali. Kalau suhu masih naik, ulangi prosedur di
atas sampai suhu tetap (tidak naik lagi).
e. Apabila penderita baru minum dingin atau panas, baru merokok,
pemeriksaan dengan cara ini harus ditunda selama 10 -15 menit dulu
agar tidak mempengaruhi hasil pengukuran.
Gambar. Pemeriksaan suhu badan melalui mulut
Pemeriksaan pada rektum:
Pemeriksaan melalui rektum ini biasanya dilakukan terhadap bayi.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 65
Buku Panduan CSL 1 2017
a. Minta pasien untuk berbaring dengan miring pada salah satu sisi
dengan pinggul menekuk.
b. Pilihlah termometer dengan ujung yang bulat, beri pelumas dan
masukkan dalam anus sedalam 3 – 4 cm (1,5 inchi) dengan arah ke
arah umbilkus.
c. Tunggulah selama 3 menit.
d. Cabut kembali termometer dan baca hasilnya.
Gambar. Pemeriksaan suhu badan rectal
Pemeriksaan pada ketiak (aksila)
a. Kibaskan termometer sampai permukaan air raksa menunjuk di bawah
35°C
b. Tempatkan ujung termometer yang berisi air raksa pada apex fossa
axillaris kiri dengan sendi bahu adduksi maksimal
c. Tunggu sampai 3 – 5 menit.
d. Cabut kembali termometer dan lakukan pembacaan.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 66
Buku Panduan CSL 1 2017
Gambar. Pemeriksaan suhu badan melalui ketiak (aksila)
Catatan: pada prakteknya untuk menghemat waktu pada saat menunggu
pengukuran suhu juga dibarengi dengan pemeriksaan nadi dan nafas
e. Cuci tangan WHO setelah pemeriksaan fisik.
G. DAFTAR PUSTAKA
Bate’s barbara. 2007. Guide to physical examination. Lippincot.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 67
Buku Panduan CSL 1 2017
5. CEKLIS LATIHAN PENILAIAN VITAL SIGN
Skor Feed Back
No Aspek
0 1 2
I INTERPERSONAL
1 Sambung Rasa (Membina rapport (menyambut
dengan ramah, salam, menyilakan duduk,
perkenalan diri, komunikasi non verbal)
2 Informed Consent
II CONTENT
A Pemeriksaan Tekanan Darah
3 Siapkan alat yang diperlukan (stetoskop dan
sphygmomanometer. Buka dan tegakkan
sphygmo manometer, buka aliran air raksanya,
cek saluran pipa)
4 Cuci tangan WHO
5 Siapkan penderita dapat dalam keadaan duduk
atau berbaring
6 Pemeriksa menempatkan diri disebelah kanan
pasien atau duduk berhadapan
7 Pastikan lengan pasien dalam keadaan bebas
dan relaks, serta bebas dari tekanan karena
pakaian.
8 Pasang manset pada lengan atas pasien
sedemikian rupa sehingga pusat dari manset
yang dapat digembungkan (bladder) berada
tepat di atas arteri brachialis, tidak longgar dan
tidak ketat, 2,5cm-5cm di atas siku
9 Posisikan lengan pasien sedikit fleksi(menekuk)
pada siku
10 Raba a. brachialis pasien, naikkan tekanan
manset sampai pulsasi tidak teraba, tambahkan
30mmHg.
11 Turunkan tekanan manset perlahan-lahan
sampai denyutan a. Brachialis teraba kembali
tekanan sistolik palpatoar (Laporkan)
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 68
Buku Panduan CSL 1 2017
12 Kempiskan manset dengan segera dan tunggu 15
sampai 30 detik
13 Ambil dan pasang stetoskop, serta letakkan
bagian bell/diafragma pada tempat perabaan
pulsasi (di atas arteri brachialis)
14 Naikkan kembali tekanan manset sampai 30 mm
Hg di atas tekanan sistolik palpatoar
15 Dengarkan melalui stetoskop sambil
menurunkan tekanan manset perlahan-lahan (2-
3 mmHg/detik). Perhatikan saat
dimana terdengar suara bising pertama
tekanan systole
16 Turunkan terus tekanan manset sampai suara
tersebut melemah kemudian menghilang
tekanan diastole
17 Kempiskan manset sampai tekanan pada
manometer menunjukkan skala nol
18 Lepas dan rapikan kembali manset, tutup aliran
air raksa serta tutup kembali
sphygmomanometernya
B Pemeriksaan Nadi
19 Siapkan pasien dapat dalam posisi duduk
ataupun berbaring, lengan pasien dalam posisi
bebas (relaks), perhiasan dan jam tangan dilepas
20 Raba a. Radialis dengan menggunakan jari
telunjuk dan jari tengah anda sehingga pulsasi
(denyutan) maksimal dapat dirasakan
21 Hitung frekuensi denyut nadi
Perhatikan pula irama dan kualitas denyutnya
C Pemeriksaan Pernafasan
22 Minta pasien untuk melepaskan pakaian
sehingga pergerakan dinding dada dapat jelas
terlihat
23 Secara inspeksi, perhatikan secara menyeluruh
gerakan pernafasan Jika tidak jelas, dapat
melalui cara palpasi dengan kedua tangan pada
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 69
Buku Panduan CSL 1 2017
punggung atau dada pasien
24 Hitung frekuesi nafas pasien selama 15 detik dan
kalikan 4 untuk mendapatkan frekuensi nafas
per menit
D Pemeriksaan Suhu
25 kibaskan termometer sampai permukaan air
raksa di bawah 35°C
261. Tempatkan ujung termometer yang berisi air
raksa pada apex fossa axillaris kiri dengan sendi
bahu adduksi maksimal
272. Tunggu selama 3 – 5 menit
283. Cabut kembali termometer dan lakukan
pembacaan
294. Cuci tangan WHO
III PROFESIONALISME
30 Laporkan hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi,
pernafasan dan suhu
31 Mampu melakukan dengan percaya diri
32 Mampu melakukan dengan kesalahan minimal
TOTAL
Nilai = ------------- x 100% = ……………
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 70
Buku Panduan CSL 1 2017
..: PENGENALAN ALAT BEDAH MINOR &
HECTING DASAR
dr. Iswandi Darwis | dr. Muhammad Aditya
A. TEMA
Pengenalan alat bedah minor
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Mahasiswa dapat mengetahui alat-alat yang digunakan dalam tindakan
bedah minor
C. ALAT DAN BAHAN
1. Needle holder
2. Gunting diseksi, gunting benang, gunting verban
3. Pisau bedah
4. Klem (arteri pean, kocher, musquitos, allis, babcock, towel clamp).
5. Refractor wound
6. Pinset
7. Deschamps Aneurysm Needle
8. Wound curret
9. Korentang
10. Jarum bedah
11. Benang
12. Sarung tangan steril
13. Doek steril
14. Kassa steril
15. Cairan disinfektan (pov. Iodine)
16. Cairan NaCl 0.9%
17. Spuit 1cc , 3 cc, 5 cc
18. Anastesi : Lidocaine 2% Ampule
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 71
Buku Panduan CSL 1 2017
D. SKENARIO
Seorang laki-laki datang ke Puskesmas dengan keluhan terdapat luka
robek di lengan kanan bawah. Anda selaku dokter di puskesmas ingin
melakukan tindakan penjahitan. Sebelum melakukan penjahitan anda
harus mengambil alat bedah minor di tempat steril. Alat-alat apa sajakah
yang diperlukan dalam tindakan bedah minor? Dan lakukanlah penjahitan
dasar.
E. DASAR TEORI
Penjahitan luka diperlukan dalam ilmu bedah karena pembedahan
membuat luka sayatan dan penjahitan bertujuan untuk menyatukan
kembali jaringan yang terputus serta meningkatkan proses penyambungan
dan penyembuhan jaringan dan juga mencegah luka terbuka yang akan
mengakibatkan masuknya mikroorganisme atau infeksi.
..: ALAT-ALAT BEDAH MINOR :..
Material penjahitan yang berkualitas adalah yang meliputi sarat-sarat
tertentu. Yang pertama adalah kenyamanan untuk digunakan atau untuk
dipegang. Lalu pengamanan yang cukup pada setiap alat. Harus selalu
steril. Cukup elastik. Bukan terbuat dari bahn yang reaktif. Kekuatan yang
cukup untuk penyembuhan luka. Kemampuan untuk biodegradasi kimia
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 72
Buku Panduan CSL 1 2017
untuk menceah perusakan dari benda asing. Berikut alat-alat yang
diperlukan untuk bedah minor.
1. Nald Voeder
Nama lainnya pemegang jarum atau needle holder. Jenis yang digunakan
bervariasi, yaitu tipe Crille Wood (bentuk seperti klem) dan tipe Mathew
Kusten (bentuk segitiga). Guna nald voeder ini pada penjahitan, sebagai
pemegang jarum jahit (nald heacting) dan sebagai penyimpul benang.
A B
Gambar. (A) Nald Voeder Tipe Crille wood dan (B) Nald Voeder Tipe
Mathew Kusten
2. Gunting
Gunting diseksi
Gunting diskesi (disecting scissor). Gunting ini ada dua jenis yaitu, lurus
dan bengkok. Ujungnya biasanya runcing. Terdapat dua tipe yang sering
digunakan yaitu tipe mayo dan tipe metzenbaum. Kegunaan gunting ini
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 73
Buku Panduan CSL 1 2017
adalah untuk membuka jaringan, membebaskan tumor kecil dari jaringan
sekitarnya, untuk eksplorasi, maupun merapikan luka.
A B
Gambar. (A) Gambar gunting tipe mayo, (B) gunting tipe metzenbaum
Gunting Benang
Ada dua macam gunting benang yaitu gunting benang yang bengkok dan
yang lurus. Kegunaannya untuk memotong benang operasi, merapikan
luka.
Gambar. Gunting benang
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 74
Buku Panduan CSL 1 2017
Gunting perban/pembalut
Kegunaannya adalah untuk menggunting pembalut dan plester.
Gambar. Gunting perban/pembalut
3. Pisau Bedah
Terdiri atas dua bagian, yaitu gagang dan mata pisau
(mess/bistouri/blade). Pada pisau bedah model lama, mata pisau dan
gagang bersatu, sehingga bila mata pisau tumpul harus diasah kembali.
Pada model baru, mata pisau dapat diganti. Biasanya mata pisau hanya
untuk sekali pakai.
Terdapat dua nomor gagang pisau yang sering dipakai, yaitu gagang nomor
4 (untuk mata pisau besar) dan gagang nomor 3 (untuk mata pisau kecil).
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 75
Buku Panduan CSL 1 2017
Guna pisau bedah ini adalah untuk menyanyat berbagai organ/bagian
tubuh. Mata pisau, disesuaikan dengan bagian tubuh yang akan disayat.
Gambar. Pisau bedah
4. Klem (clamp)
Klem arteri pean
Ada dua jenis yaitu yang lurus dan bengkok. Penggunaannya adalah untuk
hemostasis terutama untuk jaringan tipis dan lunak. Penyediaan : masing-
masing 6 buah.
Gambar. Klem arteri pean
Klem Kocher
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 76
Buku Panduan CSL 1 2017
Ada dua jenis yaitu, klem yang lurus dan yang bengkok. Tidak ditujukan
untuk hemostatis. Sifat khasnya adalah mempunyai gigi pada ujungnya
(mirip gigi pada pinset sirurgis). Gunanya adalah untuk menjepit
jaringannya, terutama agar jaringan tidak meleset dari klem, dan hal ini
dimungkinkan dengan adanya gigi pada ujung klem. Penyediaannya :
masing-masing 4 buah.
Gambar. Klem Kocher
Klem Mosquito
Mirip dengan klem arteri pean, tetapi ukurannya lebih kecil.
Penggunaannya adalah untuk hemostatis terutama untuk jaringan tipis
dan lunak. Penyediaannya : masing-masing 6 buah.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 77
Buku Panduan CSL 1 2017
Gambar. Klem Mosquito
Klem Allis
Penggunaannya adalah untuk menjepit jaringan yang halus dan menjepit
tumor kecil.
Gambar. Klem Allis
Klem Babcock
Penggunaannya adalah untuk menjepit tumor yang agak besar dan rapuh.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 78
Buku Panduan CSL 1 2017
Gambar. Klem Babcock
Towel Clamp (Doek Klem). Penggunaannya adalah untuk menjepit
doek/kain operasi.
Gambar. Towel Clamp
5. Retractor (Wound Hook)
Retractor Langenbeck
Penggunaannya adalah untuk menguakkan luka.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 79
Buku Panduan CSL 1 2017
Gambar. Retractor Langenbeck
Retractor Volkman
Penggunaannya adalah untuk menguakkan luka, pemakaian retractor
(ukurannya) disesuaikan dengan lebar luka. Ada yang mempunyai 2 gigi, 3
gigi dan 4 gigi. Dua gigi untuk luka kecil, 4 gigi untuk luka besar. Terdapat
pula retractor bergigi tumpul.
Gambar. Retractor Volkman
6. Pinset
Pinset Sirurgis
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 80
Buku Panduan CSL 1 2017
Penggunaannya adalah untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan
penjahitan luka, memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi.
Pinset Anatomis
Penggunaannya adalah untuk menjepit kasa sewaktu menekan luka,
menjepit jaringan yang tipis dan lunak.
Pinset Splinter
Penggunaannya adalah untuk mengadaptasi tepi-tepi luka (mencegah
overlapping).
Gambar. Pinset
7. Deschamps Aneurysm Needle
Penggunaannya adalah untuk mengikat pembuluh darah besar.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 81
Buku Panduan CSL 1 2017
Gambar. Deschamps Aneurysm Needle
8. Wound Curett
Penggunaannya adalah untuk mengeruk luka kotor, mengeruk ulkus kronis
Gambar. Wound Curett
9. Korentang
Penggunaannya adalah untuk mengambil instrument steril, dan mengambil
kasa, jas operasi, doek dan laken steril.
Gambar. Korentang
10. Jarum Bedah
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 82
Buku Panduan CSL 1 2017
Jarum bedah berfungsi untuk mengantarkan benang pada saat melakukan
penjahitan luka operasi.
Klasifikasi
• Pemilihan jarum bedah antara lain : jarum yang digunakan agar
berperan aktif dalam penyembuhan luka dan tidak merubah atau
merusak jaringan tubuh. Bentuk, ukuran, dan rancangan jarum dipilih
yang sesuai dengan prosedur operasi. Terdapat 2 macam jarum bedah
dilihat dari penggunaan benang yaitu berupa jarum lepas dan jarum
atraumatik
o Jarum lepas
▪ Memerlukan waktu penyambungan benang dengan
jarum
▪ Memerlukan re–sterilisasi
▪ Memerlukan perawatan ujung jarum
▪ Resiko jarum berkarat
▪ Resiko benang terlepas dari jarum
▪ Pemilihan jarum harus tepat dengan benang
o Jarum bedah atraumatik
▪ Benang bedah menyatu dengan jarum sekaligus
▪ Penyambungan benang bedah dengan jarum secara
channelateau drilled
▪ Benang tunggal sehingga menimbulkan trauma yang
minimal pada jaringan
▪ Dijamin steril dan bebas karat
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 83
Buku Panduan CSL 1 2017
▪ Sekali pakai buang sehingga tidak perlu re-sterilisasi
Struktur Jarum Bedah
Gambar. stuktur jarum bedah
• Bagian – bagian dari jarum bedah, terdiri atas:
o Ujung jarum (point of needle)
o Badan / Batang (body/shaft needle)
o Mata jarum (eye needle)
a. Ujung jarum (point of needle)
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 84
Buku Panduan CSL 1 2017
• Taper. Ujung jarum taper dengan batang bulat atau empat persegi
cocok digunakan untuk menjahit daerah aponeurosis, otot, saraf,
peritoneum, pembuluh darah, katup.
• Blunt. blunt point dan batang gepeng cocok digunakan untuk
menjahit daerah usus besar, ginjal, limpa, hati
• Triangular. Ujung segitiga dengan batang gepeng atau empat
persegi. Bisa dipakai untuk menjahit daerah kulit, fascia, ligament,
dan tendon.
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 85
Buku Panduan CSL 1 2017
• Tapercut. Ujung jarum berbentuk segitiga yang lebih kecil dengan
batang gepeng, bisa digunakan untuk menjahit fascia, ligaments,
uterus, rongga mulut, dan sebagainya.
b. Badan atau batang
• Straight. Digunakan untuk daerah kulit, nervus, saluran
pencernaan, tendon, pembuluh darah, dan sebagainya.
• Halfcurved. Digunakan untuk kulit (tetapi jarang dipakai)
o Curved dibagi atas:
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 86
Buku Panduan CSL 1 2017
▪ 1/4 circle – mata, bedah mikro
▪ 3/8 circle – dipakai pada hampir seluruh tubuh
▪ 1/2 circle – dipakai pada hampir seluruh tubuh
▪ 5/8 circle – traktus urinarius dan system
reproduksi
• Combine needle – daerah mata bagian anterior
c. Mata jarum
• Rolled end
• Drilled end
• Regular eye
• Spring eye
• Spring double eyes
Buku Panduan Keterampilan Klinik Semester 1 87
Buku Panduan CSL 2 2017
11. Benang bedah
Benang bedah (suture) adalah materi berbentuk benang yang berfungsi untuk ligasi (mengikat) pembuluh
darah atau aproksimasi (mengikat/menyatukan jaringan).
Spesifik material benang bedah
• Steril, dan harus steril sewaktu digunakan.
• Diketahui kekuatan untuk memegang jaringan (tensil strength) yang sesuai jenis material benang.
• Diketahui massa penyerapan yaitu lamanya benang habis diserap tubuh
• Simpul aman, diketahui jumlah minimal tali simpul yang aman untuk setiap jenis benang, artinya
tetap tersimpul selama proses penyembuhan luka.
• Mudah untuk digunakan.
• Dapat digunakan untuk segala jenis operasi.
• Reaksi/trauma jaringan yang minimal, diameter benang bedah yang dianjurkan dipergunakan adalah
ukuran terkecil yang paling aman untuk setiap jenis jaringan yang dijahit, massa material benang dan
reaksi jaringan sekecil mungkin.
Ukuran benang bedah
• Ukuran terbesar adalah 7 dan ukuran terkecil adalah 11-0 atau 12-0.
• Ukuran dimulai dari nomor 1 dan ukuran bertambah besar dengan bertambah 1, sedangkan apabila
ukuran bertambah kecil maka ditambah 0.
• Ukuran benang sistem Eropa (metric gauge) adalah metric 0,1 (0,010 – 0,019 mm) sampai metric 10
(1,00 – 1,09).
• Ukuran benang sistem Amerika (imperial gauge) ukuran 11-0 (0,010 – 0,019 ) sampai ukuran 7 (1,00 –
1,09).
• Dalam kemasan selain dicantumkan diameter juga panjang benang dalam cm.
Klasifikasi Benang Bedah
A. Berdasarkan keberadaannya didalam tubuh pasien dibagi atas :
o Diserap (absorbable sutures)
Merupakan jenis benang yang materialnya dibuat dari jaringan collagen mamalia sehat atau dari
sintetik polimer. Material di dalam tubuh akan diserap yang lamanya bervariasi, sehingga tidak ada
benda asing yang tertinggal di dalam tubuh.
o Tidak diserap (non ansorbable sutures)
▪ Merupakan benang yang dibuat dari material yang tahan terhadap enzim penyerapan dan tetap
berada dalam tubuh atau jaringan tanpa reaksi penolakan selama bertahun – tahun.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 88
Buku Panduan CSL 2 2017
▪ Kelebihan dari benang ini adalah dapat memegang jaringan secara permanen. Kekurangan dari
benang ini adalah benang ini menjadi benda asing yang tertinggal didalam tubuh dan
kemungkinan akan menjadi fistel.
B. Berdasarkan materi / bahan, dibagi atas :
a. Bahan alami, dibagi atas :
i. Diserap (absorbable)
Dibuat dari collagen yang berasal dari lapisan sub. Mukosa usus domba dan serabut collagen
tendon flexor sapi.
Contoh :
a. Surgical catgut plain : Berasal dari lapisan sub. Mukosa usus domba dan serabut
collagen tendon flexor sapi tanpa campuran.
b. Surgical catgut chromic : Berasal dari lapisan sub. Mukosa usus domba dan serabut
collagen tendon flexor sapi dicampur dengan chromic aci
ii. Tidak diserap (non absorbable sutures)
Jenis ini terbuat dari linen, ulat sutra (silk) seperti surgical silk, virgin silk dan dari kapas
(cotton) seperti surgical cotton. Ada juga yang terbuat dari logam sehingga mempunyai tensil
strength yang sangat kuat, contoh : metalik sutures (stainless steel).
b. Bahan sintetis (buatan), dibagi atas :
i. Diserap (absorbable)
Terbuat dari sintetik polimer, sehingga mudah diserap oleh tubuh secara hidrolisis dan waktu
penyerapan oleh tubuh mudah diprediksi,
contoh :
a. Polyglactin 910
b. Polylactin 910 polylastctin 370 dan calcium state (Coated Vicryl®)
c. Polylactin 910 polylastctin 370 dan calcium state (Vicryl Rapide®)
d. Poliglikolik
e. Polyglecaprone 25 (Monocryl®)
f. Polydioxanone (PDS II®)
ii. Tidak diserap (non absorbable)
Terbuat dari bahan buatan (sintetis) dan dibuat sedemikian rupa sehingga reaksi jaringan
yang timbul sangat kecil,
contoh :
a. Polypropamide (Ethilon®)
b. Polypropylene (Prolene®)
c. Polyester (Mersilene®)
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 89
Buku Panduan CSL 2 2017
C. Berdasarkan penampang benang, dibagi atas :
a. Monofilamen (satu helai)
i. Terbuat dari satu lembar benang, tidak meneyerap cairan (non capilarity)
ii. Keuntungan : Kelebihan dari jenis ini adalah permukaan benang rata dan halus, tidak
memungkinkan terjadinya nodus infeksi dan tidak menjadi tempat tumbuhnya mikroba.
iii. Kelemahan : Kelemahannya adalah memerlukan penanganan simpul yang khusus karena
relatif cukup kaku dan tidak sekuat multifilament.
iv. Contoh : Catgut, PDS, dan Prolene
b. Multifilamen
i. Terbuat dari bebeapa filament atau lembar bahan benang yang dipilih menjadi satu.
ii. Keuntungan : Kelebihan jenis ini adalah benang lebih kuat dari monofilament, lembut dan
teratur serta mudah digunakan.
iii. Kerugian : Kelemahannya adalah karena ada rongga maka dapat menjadi tempat
menempelnya mokroba dan sedikit tersendat pada saat melalui jaringan.
iv. Contoh : Vicryl, Silk, Ethibond
Pemilihan material benang bedah
• Karakteristik biologi dari material dalam jaringan yaitu diserap atau tidak diserap dan bersifat
capilarity atau non capilarity.
• karakteristik dan penyembuhan jaringan.
• Lokasi dan panjang dari sayatan yang menjadi pertimbangan kosmetik.
• Ada tidaknya infeksi, kontaminasi dan drainese. Pertimbangan ini mengingat kemungkinan benang
akan menjadi pembentukan jaringan granulasi dan proses yang menjadi rongga (sinus) atau menjadi
inti pengerasan yang kemungkinan berbentuk batu apabila dipakai pada operasi kandung kemih atau
kandung empedu.
• Problem pasien seperti kegemukan, debil, umur penyakit lain yang mengganggu proses penyembuhan
yang lebih lama sehingga memerlukan penguatan yang lebih lama.
• Karakteristik fisik dari material benang untuk menembus jaringan, pengikatan simpul dan juga alasan
khusus tiap ahli bedah.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 90
Buku Panduan CSL 2 2017
Jenis-Jenis Benang
a. Seide (Silk/Sutera)
Terbuat dari serabut-serabut sutera, terdiri dari 70% serabut protein dan 30% bahan tambahan berupa
perekat. Tersedia dalam warna hitam dan putih. Bersifat tidak licin seperti sutera biasa karena sudah
dikombinasi dengan perekat, tidak diserap tubuh. Pada penggunaan disebelah luar, maka benang harus
dibuka kembali.
Tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari nomor 0000 (5 nol merupakan ukuran paling kecil) hingga
nomor 3 (yang merupakan ukuran terbesar). Yang paling sering dipakai adalah nomor 00 (2 nol) dan 0 (1
nol) dan nomor 1
Kegunaannya adalah untuk menjahit kulit, mengikat pembuluh arteri (terutama arteri besar) sebagai
teugel (kendali). Benang harus steril, sebab bila tidak akan menjadi sarang kuman (focus infeksi) sebab
kuman terlindung didalam jalinan benang, sedang benangnya sendiri tidak dapat diserap tubuh.
b. Plain Catgut
Asal katanya adalah cat (kucing), dan gut (usus). Dahulu benang ini dibuat dari usus kucing, tapi saat ini
dibuat dari usus domba atau usus sapi. Bersifat dapat diserap tubuh, penyerapan berlangsung dalam
waktu 7-10 hari, dan warnanya putih dan kekuningan.
Tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 00000 (5 nol merupakan ukuran yang paling kecil) hingga
nomor 3 (merupakan ukuran yang paling besar). Sering digunakan nomor 000 (3 nol), 00 (2 nol) 0 (1 nol)
nomor 1 dan 2. Kegunaanya adalah untuk mengikat sumber perdarahan kecil, menjahit subkutis dan
dapat pula dipergunakan untuk menjahit kulit terutama untuk daerah longgar (perut, wajah) yang tak
banyak bergerak dan luas lukanya kecil.
Plain catgut harus disimpul paling sedikit 3 kali, karena dalam tubuh akan mengembang, bila disimpulkan
2 kali akan terbuka kembali. Plain catgut tak boleh terendam dalam lisol karena akan mengembang dan
menjadi lunak, sehingga tak dapat digunakan.
c. Chromic Catgut
Berbeda dari plain catgut, sebelum benang dipintal ditambahkan krom. Dengan adanya krom ini, maka
benang menjadi lebih keras dan kuat, serta penyerapannya lebih lama, haitu 20-40 hari. Warnanya coklat
dan kebiruan. Benang ini tersedia dalam ukuran 000 (3 nol merupakan ukuran yang paling kecil) hingga
nomor 3.
Penggunaannya pada penjahitan luka yang dianggap belum merapat dalam waktu 10 hari, untuk menjahit
tendo pada penderita yang tak kooperatif dan bila mobilisasi harus segera dilakukan.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 91
Buku Panduan CSL 2 2017
d. Etnilon
Merupakan benang sintetis dalam kemasan atraumatis (benang langsung bersatu dengan jarum jahit) dan
terbuat dari nilon, lebih kuat dari seide atau catgut. Tidak diserap tubuh, dan tidak menimbulkan iritasi
pada kulit dan jaringan tubuh lainnya.
Tersedia dalam warna biru dan hitam. Tersedia dalam ukuran 10 nol hingga 1 nol. Penggunaannya pada
bedah plastik, ukuran yang lebih besar sering digunakan pada kulit, sedang nomor yang kecil dipakai pada
bedah mata.
f. Ethibond
Merupakan benang sintesis (terbuat dari polytetra methylene adipate). Tersedia dalam kemasan
atraumatis. Bersifat lembut, kuat, reaksi terhadap tubuh minimum, tidak diserap, dan warnanya hijau dan
putih. Ukurannya dari 7 nol hingga nomor 2. Penggunaannya pada bedah kardiovaskuler dan urologi.
g. Vitalene
Merupakan benang sintetis (terbuat dari polimer profilen). Sangat kuat dan lembut, tidak diserap, warna
biru. Tersedia dalam kemasan atraumatis. Ukuran dari 10 nol hingga nomor 1. Digunakan pada bedah
mikro, terutama untuk pembuluh darah dan jantung, bedah mata, bedah plastik, cocok pula untuk
menjahit kulit
h. Vicryl
Merupakan benang sintetis dalam kemasan atraumatis. Diserap oleh tubuh, dan tidak menimbulkan reaksi
pada jaringan tubuh. Dalam subkutis bertahan selama 3 minggu, dalam otot bertahan selama 3 bulan.
Benang ini sangat lembut dan warnanya ungu. Ukuran dari 10 nol hingga nomor 1. Penggunaan pada
bedah mata, ortopedi, urologi dan bedah plastik.
i. Supramid
Merupakan benang sintetis, dalam kemasan atraumatis. Bersifat kuat, lembut, fleksibel, reaksi tubuh
minimum, dan tidak diserap. Warnanya hitam dan putih. Digunakan untuk menjahit kutis dan sub kutis.
j. Linen (Catoon)
Dibuat dari serat kapas alam dengan jalan pemintalan. Bersifat lembut, cukup kuat, mudah disimpul, tidak
diserap, reaksi tubuh minimum. Warnanya putih. Tersedia dalam ukuran 4 nol hingga 1 nol. Digunakan
untuk menjahit usus dan kulit, terutama kulit wajah.
k. Steel Wire
Merupakan benang logam yang terbuat dari polifilamen baja tahan karat. Sangat kuat, tidak korosif dan
reaksi terhadap tubuh minimum. Mudah disimpul. Warna putih metalik. Terdapat dalam kemasan
atraumatis dan kemasan biasa. Ukurannya dari 6 nol hingga nomor 2. Untuk menjahit tendo
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 92
Buku Panduan CSL 2 2017
12. Keperluan rutin bedah
a. Baju Kamar Bedah, Jas Operasi, Topi, Masker, Doek dan Laken
Pada umumnya semua alat diatas terbuat dari kain yang ringan, lembut, yang nyaman bila dipakai, mudah
menyerap keringat dan mudah dicuci. Untuk itu dapat dipakai kain belacu atau katun. Warna alat-alat
diatas harus lembut dan tidak cepat melelahkan mata. Biasanya dipilih warna putih, biru muda, dan hijau.
Saat ini masker yang sering dipakai mempunyai model sekali pakai (disposable) yang terbuat dari kertas.
Masker ini akan dibuang sesudah digunakan. Untuk alat tenun dari kain, sesudah dipakai harus direndam
lalu dicuci. Setelah kering baru disterilkan. Masker, topi dan baju kamar bedah tidak perlu disterilkan.
b. Sarung Tangan Operasi
Terbuat dari karet, tipis tetapi cukup kuat dan elastic. Sarung tangan harus dibubuhi talcum sebelum
disterilkan, agar mudah dipergunakan. Sarung tangan tersedia dalam berbagai nomor, disesuaikan dengan
ukuran tangan pemakai
c. Kasa Hidrofil
Adalah kain dengan anyaman jarang (kasa), lembut dan bersifat mudah menyerap. Digunakan untuk
penyerap darah yang keluar dari luka, menyerap sekret dan cairan lain serta digunakan sebagai penutup
luka (dressing). Kasa ini tersedia dalam ukuran kecil-kecil, yaitu kira-kira 5 x 7,5 cm, terlipat rapi, tidak
boleh ada bagian benang yang menjulur keluar, sebab dapat tertinggal pada luka sewaktu membersihkan
luka. Kasa harus steril.
d. Tuffer (spons)
Dibuat dari kasa hidrofil yang dipadatkan dengan cara :
1. Kasa dipotong berbentuk segi empat sesuai dengan ukuran yang diinginkan
2. Dari salah satu sudutnya dilakukan penggulungan secara padat ke arah tengah
3. Ekor tadi digulung rapi hingga habis
Tuffer digunakan untuk membebaskan jaringan (terutama jaringan longgar), menekan perdarahan,
menggosok luka. Tuffer harus steril sebelum dipakai.
e. Drain
Terdapat bermacam-macam drain. Prinsip penggunaannya sama yaitu untuk memungkinkan pengaliran
sekret keluar dari luka. Drain digunakan untuk luka yang terkontaminasi dengan kemungkinan
terbentuknya pus atau sekret lainnya, atau pada luka dengan perdarahan hebat sewaktu telah ditutup ada
kemungkinan perdarahan masih aktif di bawah jaringan yang ditutup.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 93
Buku Panduan CSL 2 2017
1. Cigarette drain. Berbentuk seperti pipa dengan panjang 5-10 cm. dipergunakan pada operasi abses
apendiks, trauma dan sebagainya, dimana sekret yang keluar diharapkan tidak terlalu banyak.
2. Corrugated drain (drain bergelombang). Dibuat dari lembaran karet khusus yang bergelombang halus
(seperti pola lembaran seng atap rumah). Dipakai pada luka sedang, yang sekretnya tidak terlalu
banyak.
3. Drain Sarung Tangan. Dibuat dari sarung tangan yang tak terpakai lagi dengan cara menggunting
sarung tangan tadi menjadi lembaran-lembaran yang kemudian digulung seperti menggulung
(melinting) rokok, kemudian dilem dengan lem karet, lalu disterilkan.
4. Tube drain. Berupa pipa panjang yang dapat dibuat dari selang infuse, sonde lambung, dan
sebagainya, dengan ujung selang yang dimasukkan ke dalam luka diberi lubang-lubang (mata) pada
sisinya. Bila ujung luar selang dihubungkan dengan wadah hampa udara (vakuum) maka drain tadi
disebut vacuum drain. Dengan adanya tekanan negative dari wadah, maka sekret akan lebih mudah
tertarik keluar.
..: HECTING DASAR :..
1. Definisi
Penjahitan luka adalah suatu tindakan untuk mendekatkan tepi luka dengan benang sampai sembuh dan
cukup untuk menahan beban fisiologis.
2. Indikasi
Setiap luka dimana untuk penyembuhannya perlu mendekatkan tepi luka.
3. Luka
Luka adalah semua kerusakan kontinnuitas jaringan akibat trauma mekanis.
Trauma tajam menyebabkan :
a. luka iris : vulnus scissum/incicivum
b. luka tusuk : vulnus punctum
c. luka gigitan : vulnus morsum
Trauma tumpul menyebabkan :
a. luka terbuka : vulnus apertum
b. luka tertutup : vulnus occlusum ( excoriasi dan hematom )
Luka tembakan menyebabkan : vulnus sclopetorum.
Klasiflkasi luka berdasar ada tidaknya kuman :
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 94
Buku Panduan CSL 2 2017
a. Clean wounds/Luka steril adalah luka bedah tanpa tanda peradangan dan tidak melibatkan organ
respirasi, gastrointestinal, ataupun traktus genitourinaria. Misalnya bedah laparoskopik, bedah pada
kulit, mata, atau vaskular.
b. Clean-contaminated wounds/ Luka steril terkontaminasi adalah luka steril dengan risiko infeksi yang
tinggi, misalnya oprasi yang melibatkan organ respirasi, gastrointestinal, ataupun traktus
genitourinaria yang dalam kondisi terkontrol, selama tanpa komplikasi pembedahan. Misalnya bedah
terbuka pada pelepasan Pin/Wire, bedah pada organ telinga, ataupun tindakan ginekologi.
c. Contaminated wounds/Luka terkontaminasi adalah luka oleh benda luar (misalnya peluru, pisau,
ataupun benda-benda tajam lainnya), ataupun kontaminasi luka yang terjadi oleh karena sejumlah
besar tumpahan isi dari gastrointestinal pada luka. Ataupun jaringan yang terinfeksi dan meradang di
sekitar luka bedah merupakan luka terkontaminasi.
d. Dirty wounds/Luka kotor/Luka terinfeksi adalah luka yang diakibatkan oleh benda asing yang
bersarang (misalnya peluru ataupun debris lainnya), luka traumatik yang diakibatkan oleh sumber
yang kotor, maupun luka yang terpapar oleh pus.
4. Alat dan Bahan
Alat (Instrumen):
a. Tissue forceps (pinset)
b. Scalpel handles dan scalpel blades
c. Suture scissors
d. Needleholders
e. Suture needles (jarum)
f. Doek Steril
g. Phantom kulit
Bahan:
a. Benang
b. Cairan desifektan : Povidon-iodidine 10 % (Bethadine )
c. Cairan Na Cl 0,9%.
d. Anestesi lokal: lidocain 2%.
e. Sarung tangan.
f. Kasa steril.
5. Cara Memegang Alat
a. Instrument tertentu seperti pemegang jarum, gunting dan pemegang kasa: yaitu ibu jari dan jari
keempat sebagai pemegang utama, sementara jari kedua dan ketiga dipakai untuk memperkuat
pegangan tangan.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 95
Buku Panduan CSL 2 2017
b. Pinset lazim dipegang dengan tangan kiri, di antara ibu jari serta jari kedua dan ketiga.
c. Jarum dipegang di daerah separuh bagian belakang.
d. Sarung tangan dipakai menurut teknik tanpa singgung (hand to hand, glove to glove)
6. Prinsip yang harus diperhatikan
a. Cara memegang kulit pada tepi luka dengan surgical forceps (pinset) harus dilakukan secara halus
dengan mencegah trauma lebih lanjut pada jaringan tersebut.
b. Ukuran kulit yang yang diambil dari kedua tepi luka harus sama besarnya.
c. Tempat tusukan jarum sebaiknya sekitar 1-3 cm dari tepi lukia. Khusus” daerah wajah 2-3mm.
d. Jarak antara dua jahitan sebaiknya kurang lebih sama dengan tusukan jarum dari tepi luka.
e. Tepi luka diusahakan dalam keadaan terbuka keluar (everted) setelah penjahitan.
F. DAFTAR PUSTAKA
1. Karakata S, Bachsinar B. 1995. Bedah Minor. Hipokrates : Jakarta
2. Ethicon Inc. Wound Closure Manual. 1994. Johnson and Johnson company.
3. Doherty, GM. 2006. Current Surgical Diagnosis and Treatment. USA : McGraw Hill.
4. Sjamsuhidajat R, De Jong Wim. 2000. Buku Ajar Ilmu Bedah. Edisi ke-2. Jakarta : Penerbit Buku
Kedokteran EGC
5. Reksoprodjo, S. 2000. Kumpulan Kuliah Ilmu Bedah. Jakarta : Binarupa Aksara.
6. Utama, HSY. 2012. Keterampilan Dasar Teknik Bedah dengan Pengetahuan Material Suture. http://
herrysetyayudha.wordpress.com diakses tanggal 20 Agustus 2012.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 96
Buku Panduan CSL 2 2017
6. PENGENALAN ALAT BEDAH MINOR
Skor Feed
No Aspek
0 1 2 Back
I INTERPERSONAL
1 Membina rapport (menyambut dengan ramah, salam, menyilakan duduk,
perkenalan diri, sikap terbuka, kesejajaran)
2 Informed consent
II CONTENT
3 Cuci Tangan WHO (simulasi)
4 12. Persiapkan alat dan bahan
13. Menyiapkan dan menyebutkan nama alat dan bahan
1. Needle holder
2. Gunting diseksi, gunting benang, gunting verban
3. Pisau bedah
4. Klem (arteri pean, kocher, musquitos, allis, babcock, towel clamp).
5. Refractor wound
6. Pinset
7. Deschamps Aneurysm Needle
8. Wound curret
9. Korentang
10. Jarum bedah
11. Benang
12. Sarung tangan steril
13. Doek steril
14. Kassa steril
15. Cairan disinfektan (pov. Iodine)
16. Cairan NaCl 0.9%
17. Spuit 1cc , 3 cc, 5 cc
18. Anastesi : Lidocaine 2%
III PROFESSIONALISM
5 Melakukan dengan penuh percaya diri
6 Melakukan dengan kesalahan minimal
TOTAL
Nilai = ------------- x 100% = ……………
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 97
Buku Panduan CSL 2 2017
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 98
Buku Panduan CSL 2 2017
..: PENGENALAN MIKROSKOP
dr. Susianti, M.Sc
A. TEMA
Keterampilan laboratorium penggunaan mikroskop cahaya
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah melalui CSL ini diharapkan mahasiswa mampu untuk:
• menyebutkan bagian-bagian mikroskop cahaya.
• menjelaskan fungsi dari bagian-bagian mikroskop cahaya.
• melakukan pemeriksaan spesimen/ preparat menggunakan mikroskop cahaya.
C. ALAT DAN BAHAN
• Mikroskop cahaya
• Preparat/slide
• Sumber arus listrik
D. SKENARIO
Pada minggu pertama perkuliahan, mahasiswa semester I mendapatkan materi tentang sel dan jaringan.
Salah satu jaringan yang dipelajari adalah jaringan epitel yang menyusun permukaan kulit. Menurut teori,
epitel pada permukaan kulit (bagian epidermis) adalah epitel berlapis gepeng. Untuk melihat hal tersebut
mahasiswa dapat mengamati preparat jaringan kulit menggunakan mikroskop.
E. DASAR TEORI
1. Kegunaan Mikroskop
Penggunaan mikroskop merupakan bagian yang sangat penting dalam berbagai cabang ilmu seperti
biologi, histologi, mikrobiologi, parasitologi dan sebagainya. Dengan bantuan mikroskop kita dapat
mengamati objek yang sangat kecil yang tidak dapat diamati hanya dengan menggunakan mata
telanjang. Struktur yang dapat diamati dengan mikroskop antara lain bentuk sel, ukuran sel, serta
susunannya. Dengan mikroskop kita juga dapat mengamati organisme yang sangat kecil atau bersifat
mikroskopik seperti parasit maupun mikroorganisme.
2. Macam-Macam Mikroskop
Ada beberapa jenis mikroskop yang dapat dipergunakan. Pada dasarnya mikroskop-mikroskop itu
dapat digolongkan menurut jenis sumber cahaya yang dipakai. Tentu yang paling banyak dipakai
adalah mikroskop cahaya (optik) yang menggunakan cahaya terlihat. Selain mikroskop cahaya biasa,
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 99
Buku Panduan CSL 2 2017
ada juga beberapa modifikasi tertentu, yaitu mikroskop interferens, dan mikroskop lapangan (medan)
gelap, mikroskop polarisasi dan mikroskop fase kontras. Semua mikroskop yang menggunakan radiasi
tak terlihat dan sinar ultraviolet serta mikroskop elektron, merupakan perkembangan yang lebih baru.
3. Mikroskop Cahaya (atau optik)
Pada dasarnya mikroskop cahaya bekerja sebagai suatu alat pembesar dua tingkat. Suatu lensa
objektif melakukan pembesaran awal, dan suatu lensa okuler ditempatkan sedemikian rupa sehingga
memperbesar bayangan pertama untuk kedua kalinya. Pembesaran seluruhnya diperoleh dengan
mengalikan kekuatan pembesaran lensa objektif dan lensa okuler. Suatu lensa kondensor tambahan
biasanya ditempatkan di bawah meja mikroskop untuk memusatkan cahaya dari sumbernya menjadi
suatu berkas sangat terang yang menyinari obyek, sehingga memberikan cahaya yang cukup untuk
mengamati bayangan yang diperbesar itu. Faktor utama dalam memperoleh bayangan yang baik
dengan mikroskop adalah daya resolusi, yaitu jarak terkecil antara dua partikel sehingga kedua
partikel tersebut tampak sebagai objek yang terpisah. Daya resolusi maksimal dari mikroskop cahaya
adalah sekitar 0,2 m, yang memberikan bayangan yang cukup baik pada perbesaran 1000-1500 kali.
Objek yang lebih kecil dari 0,2 m tidak dapat dibedakan dengan alat ini. Kualitas bayangan, kejelasan
dan rincian bergantung pada daya resolusi mikroskop. Pembesaran hanya akan bermanfaat jika
dibarengi dengan resolusi yang tinggi. Daya resolusi sebuah mikroskop terutama bergantung pada
lensa objektifnya. Lensa okuler hanya memperbesar bayangan yang diperoleh dari lensa objektif, tidak
mempertinggi resolusi. Ukuran spesimen yang diamati dapat diperoleh dengan mengalikan
perbesaran lensa okuler dengan lensa objektif, misal: Okuler (10X) x Objektif (40X) = 400X.
4. Bagian-Bagian Mikroskop Cahaya
Mikroskop cahaya terdiri dari dua bagian besar, yaitu:
• Bagian optik, yang berhubungan langsung dengan cahaya, terdiri dari: cermin, kondensor, lensa
objektif, lensa okuler, tubus (di antara lensa objektif dan okuler).
• Bagian mekanik, penyokong terhadap bagian optik dan mengadakan mekanisme untuk dapat
merubah jarak antara alat-alat bagian optik dan sediaan.
Berikut merupakan gambar mikroskop cahaya serta bagian-bagiannya dan fungsi masing-masing
bagian tersebut:
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 100
Buku Panduan CSL 2 2017
11
13 12
16
14
18
15
20
17
21
19
Sumber: Olympus® Instruction Manual, dimodifikasi
NO NAMA BAGIAN MIKROSKOP FUNGSI
1 Tombol utama (Main switch) Untuk menghidupkan dan mematikan mikroskop
2 Sekrup pengatur intensitas cahaya (Light Mengatur kuat lemahnya intensitas cahaya dari lampu
intensity adjustment knob) mikroskop
3 Pemegang spesimen (Specimen holder) Memfiksasi dan menggerakkan preparat dengan aman pada
meja
4 Penggerak slide horizontal dan vertikal (X- Menggerakkan preparat ke depan dan belakang, serta ke kiri
axis/ Y-axis feed knob) dan ke kanan
5 Pemutar lensa objektif (revolving nosepiece) Memutar lensa objektif sesuai posisi (perbesaran) yang
diinginkan
6 Sekrup pengatur fokus kasar dan halus Memfokuskan spesimen secara cepat dan secara lambat
(Coarse/fine adjustment knobs)
7 Tabung binokuler (Binokuler tube) Tempat kedua lensa objektif
8 Cincin pengatur diopter (Diopter adjustment Mengkompensasi perbedaan pandangan antara kedua mata
ring)
9 Cincin diafragma apertura (Aperture iris Mengatur jumlah cahaya yang masuk melalui celah pada meja
diaphragm ring) objek
10 Filter Mengkondisikan cahaya dari cahaya lampu menjadi natural
11 Sekrup pengunci kepala (Observation tube Mengunci kepala setelah diputar
clamping knob)
12 Pre focusing knob Mengatur mekanisme untuk mencegah tabrakan antara
spesimen dan lensa objektif, membatasi gerakan naik maupun
turun meja saat memfokuskan
13 Kepala (head) Menahan lensa okuler
14 Lengan Menahan kepala dan meja
15 Meja (stage) Tempat meletakkan spesimen
16 Lensa okuler (Eyepiece / oculars) Memperbesar bayangan objek (biasanya 10x) dan diproyeksikan
ke retina.
17 Kondenser (condenser) Mengumpulkan dan memfokuskan cahaya sehingga terbentuk
kerucut cahaya yang mengiluminasi objek yang diamati
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 101
Buku Panduan CSL 2 2017
18 Lensa objektif Memperbesar (biasanya 4x,10x,40x dan 100x) dan meneruskan
bayangan objek teriluminasi ke arah lensa okuler
19 Sumber cahaya Mengiluminasi spesimen
20 Sekrup pengatur ketinggian kondenser Menaikkan dan menurunkan kondenser
(Condenser height adjustment knob)
21 Dasar (base) Menyokong mikroskop
F. PROSEDUR PENGGUNAAN MIKROSKOP CAHAYA
1. Mengambil mikroskop dari lemari penyimpanan
• Bawalah mikroskop dengan menggunakan kedua tangan (tangan yang satu memegang lengan
mikroskop, dan yang satu lagi memegang dasar mikroskop), dan taruh di meja yang datar.
Pehatikan gambar di bawah!
Sumber: Alexander, S.K. 2004
• Bukalah sarung/ pembungkus mikroskop
2. Menyalakan mikroskop
• Hubungkan kabel mikroskop ke sumber arus listrik.
• Nyalakan mikroskop dengan menekan tombol utama pada posisi ‘’I’’.
• Atur intensitas cahaya dengan memutar sekrup pengatur intensitas cahaya sesuai yang
dikehendaki (angka di sekeliling sekrup menandakan watt).
3. Meletakkan spesimen pada meja mikroskop
• Putar sekrup pengatur fokus kasar ke arah yang berlawanan dengan jarum jam sampai posisi
meja paling rendah.
• Buka penjepit preparat sambil terus di tahan, letakkan spesimen pada meja mikroskop dari arah
depan, dan lepaskan penjepit preparat dengan hati-hati sehingga posisi spesimen terfiksasi.
➢ Spesimen yang dimaksud biasanya berupa preparat (slide) yang terdiri dari gelas objek (slide
glass/object glass) dan gelas penutup (cover glass).
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 102
Buku Panduan CSL 2 2017
Sumber: Olympus® Instruction Manual
• Gunakan penggerak slide horizontal dan vertikal untuk mengatur spesimen supaya berada di
tengah tepat di atas kondenser.
4. Mengatur fokus
• Putar pemutar lensa objektif dan posisikan lensa objektif pada perbesaran 4X.
• Setelah lensa objektif tersebut tepat di atas spesimen, gerakkan sekrup pengatur fokus kasar
searah jarum jam sampai meja berada sedekat mungkin dengan lensa objektif.
• Sambil melihat melalui lensa okuler gerakkan sekrup pengatur fokus kasar berlawanan dengan
arah jarum jam secara perlahan untuk menambah jarak antara lensa objektif dan spesimen, dan
berhentilah saat gambar spesimen telah terlihat fokus.
• Sambil melihat melalui lensa okuler gerakkan kedua tabung binokuler untuk mengatur jarak
interpupil, sehingga gambar yang dilihat antar kedua mata menyatu.
• Tutuplah mata kiri dan gunakan mata kanan untuk memfokuskan gambar dengan memutar
sekrup pengatur fokus kasar dan halus, sampai terlihat fokus (jika diperlukan).
• Tutuplah mata kanan dan gunakan mata kiri untuk memfokuskan gambar dengan memutar cincin
pengatur diopter pada lensa okuler kiri, sampai fokus (jika diperlukan).
• Bukalah kedua mata dan untuk memfokuskan kembali gerakkan sekrup pengatur fokus halus
untuk memperoleh gambar yang paling jelas.
5. Mengatur posisi kondenser dan diafragma apertura (jika diperlukan)
• Putar pengatur tinggi kondensor (lihat gambar di bawah) untuk menggerakkan kondenser pada
posisi paling tinggi (cahaya penuh).
• Cincin diafragma apertura (lihat gambar di bawah) memiliki skala perbesaran objektif (4X, 10X,
40X, 100X). Putarlah cincin tersebut sehingga skala perbesaran objektif yang digunakan berada di
arah depan.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 103
Buku Panduan CSL 2 2017
Sumber: Olympus® Instruction Manual
1. Pengatur tinggi kondensor, 2. Cincin diafragma apertura
6. Memindahkan lensa objektif untuk pengamatan
• Pegang dan putar pemutar lensa objektif, sehingga objektif yang akan digunakan (sesuai dengan
perbesaran yang diinginkan: 10X, 40X, 100X) berada di atas spesimen.
• Putar sekrup pengatur fokus halus untuk memfokuskan gambar sampai terlihat jelas.
• Amatilah spesimen/preparat dengan detil dan geser spesimen menggunakan penggerak slide
horizontal dan vertikal untuk mengamati seluruh bagian preparat tersebut.
7. Mengambil spesimen dari meja mikroskop
• Jika pengamatan telah selesai, posisikan kembali lensa objektif pada perbesaran 4X.
• Bukalah penjepit preparat sambil terus di tahan, ambil spesimen pada meja mikroskop dari arah
depan, dan lepaskan penjepit preparat.
8. Mematikan mikroskop
• Matikan lampu mikroskop dengan menekan tombol utama pada posisi ‘’O’’.
• Lepaskan kabel dari sumber arus listrik.
9. Menyimpan mikroskop ke tempat penyimpanan
• Pasang kembali sarung/ pembungkus mikroskop.
• Masukkan mikroskop ke lemari penyimpanan (cara membawanya sama dengan saat
mengambilnya).
10. Penggunaan minyak immersi (untuk perbesaran objektif 100X)
Semakin kecil nilai daya pisah, akan semakin kuat kemampuan lensa untuk memisahkan dua titik yang
berdekatan pada preparat sehingga struktur benda terlihat lebih jelas. Daya pisah dapat diperkuat
dengan memperbesarkan indeks bias atau menggunakan cahaya yang memiliki panjang gelombang
(λ) pendek. Biasanya dapat digunakan minyak imersi untuk meningkatkan indeks bias pada
perbesaran 10 X 100. Caranya adalah sebagai berikut:
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 104
Buku Panduan CSL 2 2017
• Jika fokus pada perbesaran 10X40 telah didapatkan maka putar ke perbesaran objektif 100X.
• tetesi minyak imersi 1 – 2 tetes dari sisi lensa.
• Jika telah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan lensa objektif 100X dengan kertas lensa
yang dibasahi xylol.
G. DAFTAR PUSTAKA
1. Olympus® Educational Microscope CX21 Instruction Manual. Olympus Optical co. Ltd. Tokyo.
2. Junqueira, L.C, Carneiro, J. 2003. Basic Histology, Tenth Edition, Lange Medical Books McGraw-Hill,
United States of America.
3. Alexander, S.K., Strete, D., and Niles, M. J. 2004. Laboratory Exercises in Organismal and Molacular
Microbiology. McGraw-Hill. United States of America.
4. Gartner, L.P., and Hiatt, J. L. 2007. Color Atlas of Histology, Fourth Edition. McGraw-Hill. United States
of America.
5. Staf Pengajar FK Unsoed. 2008. Petunjuk Praktikum Mikrobiologi Dasar.. Fakultas Kedokteran Unsoed.
Semarang
6. Staf Pengajar FK Unila. 2003. Buku Praktikum Histologi Bagian I.. Program Studi Pendidikan Dokter
Unila. Bandar Lampung
CHECKLIST LATIHAN PENGENALAN MIKROSKOP
Skor Feed Back
No Aspek
0 1 2
A Mengambil mikroskop dari lemari penyimpanan
1 Bawalah mikroskop dengan menggunakan kedua tangan
(tangan yang satu memegang lengan mikroskop, dan yang
satu lagi memegang dasar mikroskop)
2 Letakkan mikroskop di meja yang datar
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 105
Buku Panduan CSL 2 2017
B Menyalakan mikroskop
3 Hubungkan kabel mikroskop ke sumber arus listrik.
4 Nyalakan mikroskop dengan menekan tombol utama pada
posisi ‘’I’’.
5 Atur intensitas cahaya dengan memutar sekrup pengatur
intensitas cahaya sesuai yang dikehendaki.
C Meletakkan spesimen pada meja mikroskop
6 Putar sekrup pengatur fokus kasar ke arah yang berlawanan
dengan jarum jam sampai posisi meja paling rendah.
7 Buka penjepit preparat sambil terus di tahan, letakkan
spesimen pada meja mikroskop dari arah depan, dan
lepaskan penjepit preparat.
D Mengatur focus
8 Gunakan penggerak slide horizontal dan vertikal untuk
mengatur spesimen supaya berada di tengah tepat di atas
condenser
9 Putar pemutar lensa objektif dan posisikan lensa objektif
pada perbesaran 4X.
10 Setelah lensa objektif tersebut tepat di atas spesimen,
gerakkan sekrup pengatur fokus kasar searah jarum jam
sampai meja berada sedekat mungkin dengan lensa
objektif.
11 Sambil melihat melalui lensa okuler gerakkan gerakkan
sekrup pengatur fokus kasar berlawanan dengan arah
jarum jam secara perlahan untuk menambah jarak antara
lensa objektif dan spesimen, dan berhentilah saat gambar
spesimen telah terlihat fokus.
12 Sambil melihat melalui lensa okuler gerakkan kedua tabung
binokuler untuk mengatur jarak interpupil, sehingga
gambar yang dilihat antar kedua mata menyatu.
13 Tutuplah mata kiri dan gunakan mata kanan untuk
memfokuskan gambar dengan memutar sekrup pengatur
fokus kasar dan halus, sampai terlihat fokus.
14 Tutuplah mata kanan dan gunakan mata kiri untuk
memfokuskan gambar dengan memutar cincin pengatur
diopter pada lensa okuler kiri, sampai fokus.
15 Bukalah kedua mata dan untuk memfokuskan kembali
gerakkan sekrup pengatur fokus halus untuk memperoleh
gambar yang paling jelas.
E Mengatur posisi kondenser dan diafragma apertura
16 Putar pengatur tinggi kondensor untuk menggerakkan
kondenser pada posisi paling tinggi (cahaya penuh).
17 Putarlah cincin diafragma apertura sehingga skala
perbesaran objektif yang digunakan berada di arah depan.
F Memindahkan lensa objektif untuk pengamatan
18 Pegang dan putar pemutar lensa objektif, sehingga objektif
yang akan digunakan (misal: 40X) berada di atas spesimen.
19 Putar sekrup pengatur fokus halus untuk memfokuskan
gambar sampai terlihat jelas.
20 Amatilah spesimen/preparat dengan detil dan geser
spesimen menggunakan penggerak slide horizontal dan
vertikal untuk mengamati seluruh bagian preparat tersebut.
G Mengambil spesimen dari meja mikroskop
21 Jika pengamatan telah selesai, posisikan kembali lensa
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 106
Buku Panduan CSL 2 2017
objektif pada pembesaran 4X.
22 Bukalah penjepit preparat sambil terus di tahan, ambil
spesimen pada meja mikroskop dari arah depan, dan
lepaskan penjepit preparat
H Mematikan mikroskop
23 Matikan lampu mikroskop dengan menekan tombol utama
pada posisi ‘’O’’.
24 Lepaskan kabel dari sumber arus listrik.
I Menyimpan mikroskop ke tempat penyimpanan
25 Pasang kembali sarung/pembungkus mikroskop.
26 Masukkan mikroskop ke lemari penyimpanan (cara
membawanya sama dengan saat mengambilnya).
27 Melakukan dengan penuh percaya diri
28 Melakukan dengan kesalahan minimal
TOTAL
Nilai = ------------- x 100% = ……………
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 107
Buku Panduan CSL 2 2017
PEMERIKSAAN SARAF
KRANIAL
A. TEMA
Pemeriksaan saraf kranial
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Mahasiswa mengetahui 12 pasang saraf kranial serta mampu menjelaskan fungsi masing-
masing.
2. Mahasiswa mampu melakukan penilaian fungsi 12 pasang saraf kranil
Level
No Jenis Kompetensi
Kompetensi
1 assessment of sense of smell 1 2 3 4
2 inspection of width of palpebral cleft 1 2 3 4
3 inspection of pupils (size and shape) 1 2 3 4
4 pupillary reaction to light 1 2 3 4
5 pupillary reaction of close objects 1 2 3 4
6 assessment of extra-ocular movements 1 2 3 4
7 assessment of diplopia 1 2 3 4
8 assessment of nystagmus 1 2 3 4
9 corneal reflex 1 2 3 4
10 assessment of visual fields 1 2 3 4
11 test visual acuity 1 2 3 4
12 fundoscopy assessment of pupil 1 2 3 3
13 assessment of facial symmetry 1 2 3 4
14 assessment of strength of temporal and masseter muscles 1 2 3 4
15 assessment of facial sensation 1 2 3 4
16 assessment of facial movements 1 2 3 4
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 108
Buku Panduan CSL 2 2017
17 assessment of taste 1 2 3 4
18 assessment of hearing (lateralization, air and bone conduction) 1 2 3 4
19 assessment of swallowing 1 2 3 4
20 inspection of palate 1 2 3 4
21 test gag reflex 1 2 3 4
22 assessment of sternokleidomastoid and trapezius muscles 1 2 3 4
23 tongue, inspection at rest 1 2 3 4
24 tongue, inspection and assessment of motor system (e.g. sticking out) 1 2 3 4
(Sumber : Standar Kompetensi Dokter (SKDI), 2012)
C. ALAT DAN BAHAN
1. Meja dan kursi tempat pemeriksaan
2. Kapas
3. Snellen chart
4. Garpu tala 512 Hz
5. Pin/jarum
6. Palu reflek
7. Pipet
8. Pen light
9. Cairan gula, garam, cuka, dan kina/kopi
10. Kopi, teh, dan tembakau
11. Ofthalmoskop
D. SKENARIO
Pasien laki-laki, 52 tahun, datang dengan keluhan nyeri kepala. Keluhan ini dirasakan sudah 3 hari.
Keluhan disertai dengan rasa kebas pada sebelah sisi kanan wajahnya. Nyeri dirasakan berdenyut-
denyut pada sisi kanan kepala, keluhan hilang timbul. Keluhan berkurang bila pasien beristirahat di
tempat yang tidak terang. Pasien belum pernah mengobati keluhannya. Untuk memastikan
diagnosis anda melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai.
E. DASAR TEORI
Secara anatomi sistem saraf pada manusia terbagi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf
perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medulla spinalis, sedangkan sistem saraf perifer
terdiri dari saraf kranial dan saraf perifer.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 109
Buku Panduan CSL 2 2017
Pemeriksaan neurologis meliputi pemeriksaan fungsi intelektual yang lebih tinggi (termasuk tingkat
kesadaran), saraf-saraf kranial, refleks, fungsi motorik, fungsi sensoris, dan fungsi serebelum.
Dari beberapa pemeriksaan neurologis yang akan dipelajari dalam blok ini adalah penilaian 12
fungsi saraf kranial
Penilaian Fungsi Saraf Kranial (Saraf Otak)
Saraf kranial merupakan saraf khusus yang keluar dari tengkorak (cranium), dan terdiri dari 12
pasang. Beberapa saraf kranial memiliki fungsi sensoris dan motoris umum, sementara yang lain
memiliki fungsi khusus seperti untuk penciuman, penglihatan maupun pendengaran. Lokasi dan
fungsi dari saraf-saraf kranial tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 1 di bawah ini:
Gambar. Bagian inferior dari otak dan saraf kranial
Tabel 1. Saraf-saraf kranial dan fungsinya
NO NAMA FUNGSI
I Olfaktorius Penciuman
II Optikus Penglihatan
III Okulomotorius Konstriksi pupil, membuka mata, pergerakan sebagian besar otot
ekstraokuler
IV Trokhlearis Pergerakan bola mata ke medial bawah
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 110
Buku Panduan CSL 2 2017
V Trigeminus Motorik: Pergerakan otot temporal dan masseter, dan pergerakan
rahang ke lateral
Sensoris: Sensasi wajah, (1) N. Ophtalmikus, (2) N. Maksilaris, (3) N.
Mandibularis
VI Abdusens Deviasi lateral mata
VII Fasialis Motorik: pergerakan wajah (ekspresi, menutup mata, menutup mulut)
Sensoris: Sensasi rasa asin, manis, asam, pahit)
VIII Akustikus Mendengar (bagian koklea), keseimbangan (bagian vestibularis)
(vestibulokoklearis)
IX Glossofaringeus Motorik: Faring
Sensoris: bagian posterior dari membran timfani dan kanalis auditorius,
faring, dan posterior dari lidah, termasuk sensasi rasa.
X Vagus Motorik: palatum, faring dan laring
Sensoris: faring, laring
XI Assesorius Motorik: Sternocleidomastoid dan bagian atas dari trapezius
XII Hipoglossus Motorik: lidah
Saraf-saraf kranial tidak diperiksa secara rutin kecuali kalau ada dugaan kuat bahwa pasien
menderita gangguan sistem saraf. Untuk mengetahui gangguan pada suatu saraf kranial (sesuai
urutan), dapat dilakukan beberapa pemeriksaan sebagai berikut:
Tabel 2. Saraf-saraf kranial dan pemeriksaannya
SARAF KRANIAL PEMERIKSAAN
I Penciuman
II - Ketajaman penglihatan (kartu Snellen)
- Lapangan pandang
- Fundus okuli
III, IV, VI - Reaksi pupil (langsung dan tidak langsung)
- Pergerakan otot ekstraokuler
V - Sensasi wajah di 3 daerah sensoris
- Menggigit dan menggerakkan rahang ke sisi berlawanan, palpasi otot
masseter dan temporal
- Reflek Sentakan Rahang
- Refleks kornea
VII - Pergerakan wajah (mengerutkan dahi, tersenyum, memperlihatkan gigi,
mengangkat alis)
- Sensoris lidah 2/3 anterior
VIII - Tes Weber dan Rinne
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 111
Buku Panduan CSL 2 2017
IX Sensoris lidah 1/3 posterior
X Pemeriksaan reflek muntah (gag refleks) dan arkus faring
V, VII, X, XII Suara dan ucapan
XI Otot sternocleidomastoid
Otot Trapezius
XII Gerakan lidah
F. PROSEDUR
1. Interpersonal
a. Membina sambung rasa (salam, senyum, sapa memperkenalkan diri)
b. Menjelaskan tujuan pemeriksaan
c. Memberikan instruksi penderita untuk duduk tegak pandangan lurus kedepan.
d. Cuci Tangan WHO
2. Inspeksi
Perhatikan kesan umum dari penderita.
3. Pemeriksaan Saraf Kranial
Nervus I. Olfaktorius
Uji Indra penciuman pada masing-masing sisi.
1. Pasien diminta menutup mata, kemudian bernafas dengan satu lubang hidung ditutup
(alternatif dengan menggunakan tangan pasien).
2. Pemeriksa mendekatkan sampel tes ke hidung pasien yang tidak ditutup. Sampel tes
sebaiknya tidak mengiritasi, seperti tembakau, teh, atau kopi.
3. Setiap lubang hidung dites bergantian.
4. Pemeriksa meminta pasien untuk melakukan inhalasi yang cukup, lalu minta pasien untuk
mengidentifikasi sampel tes.
Nervus II. Optikus
1. Kaji Tajam Penglihatan
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 112
Buku Panduan CSL 2 2017
Gambar. Pemeriksaan Tajam Penglihatan
a. Posisikan pasien pada jarak 20 kaki (6 meter) dari Snellen chart. (Jika pasien memakai
kacamata sebagai alat bantu pengelihatan, maka pasien dapat memakai kacamatanya)
b. Periksa dilakukan pada mata kanan terlebih dahulu, mata kiri ditutup dengan penutup
mata (alternatif: pasien diminta untuk menutup mata dengan tangannya)
c. Minta pasien untuk membacakan baris huruf hingga baris huruf terkecil yang masih bisa
dibaca.
d. Catat hasil pengukuran tajam pengelihatan dalam bentuk pecahan. (Misalnya 20/60,
dimana pembilang (20 kaki) adalah jarak pemeriksaan yang dipakai dalam
pemeriksaan, dan penyebut (60 kaki) adalah angka besaran huruf yang tertera pada
baris huruf Snellen chart.)
e. Ulangi prosedur untuk pemeriksaan mata kiri.
Jika pasien tidak dapat melihat huruf terbesar pada Snellen chart, maka lakukan prosedur
berikut:
• Pemeriksa mengangkat satu tangannya dan ekstensikan dua atau lebih jari, minta
pasien untuk menghitung jari pemeriksa. Apabila pasien tidak dapat menghitung jari
pemeriksa, maka pemeriksa mendekatkan diri ke arah pasien dan kembali meminta
pasien untuk menghitung jari pemeriksa. Catat pada jarak berapa pasien dapat
menghitung jari pemeriksa.
Normalnya menghitung jari (jari dapat dilihat secara terpisah) dapat dilakukan dengan
baik hingga jarak 60 meter.
• Jika pasien tidak dapat menghitung jari pemeriksa pada jarak 1 meter dari pasien,
periksa apakah pasien dapat melihat gerakan/lambaian dan dapat menentukan arah
gerakan/lambaian.
Normalnya lambaian/gerakan tangan dapat dilihat secara baik hingga jarak 300 meter.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 113
Buku Panduan CSL 2 2017
• Jika pasien tidak dapat melihat gerakan tangan, gunakan pen-light untuk memeriksa
apakah pasien dapat melihat cahaya. Catat respon pasien terhadap cahaya: persepsi
cahaya, persepsi arah cahaya, persepsi tanpa cahaya. Jika pasien tidak dapat melihat
cahaya maka visus pasien adalah 0 atau No Light Perception (NLP).
2. Lapang Pandang (Konfrontasi)
Gambar. Pemeriksaan Lapang Pandang
a. Mintalah pasien duduk dihadapan petugas pada jarak jangkauan tangan ( 30 – 50 cm )
b. Minta pasien untuk menutup mata kiri dengan tangan kirinya.
c. Pemeriksa menutup mata di sisi yang sama dengan mata pasien yang ditutup.
d. Minta pasien untuk menatap tepat pada mata pemeriksa (fiksasi).
e. Mintalah pasien agar memberi respon bila melihat objek yang digerakkan petugas di
mana mata tetap terfiksasi dengan mata pemeriksa.
f. Gerakkan objek (dapat berupa jari pemeriksa atau pena) dari perifer ke tengah di mulai
dari arah superior, superior temporal, temporal, temporal inferior, inferior, inferior nasal,
superior nasal.
g. Bandingkan dengan lapang pandang pemeriksa.
h. Ulangi langkah tersebut pada pemeriksaan mata kiri.
3. Funduskopi
Gambar. Pemeriksaan Funduskopi
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 114
Buku Panduan CSL 2 2017
Pemeriksaan funduskopi di bidang neurologi bertujuan untuk menilai keadaan fundus okuli
terutama retina dan papil nervus optikus. Pemeriksaan dilakukan pada ruangan yang
temaran dan pasien diberikan midriatikum sebelumnya.
a. Pemeriksa memegang oftalmoskop dengan tangan kanan untuk memeriksa mata kiri
pasien (untuk memeriksa mata kanan pasien dengan memegang oftalmoskop pada
tangan kiri), pemeriksa memposisikan jari telunjuk pada pengatur lensa.
b. Menyalakan oftalmoskop, memegang dengan menempel pada mata. Lalu perlahan
bergerak maju mendekati pasien dengan oftalmoskop diposisikan pada sisi temporal
pasien hingga gambaran fundus terlihat.
c. Jari telunjuk yang terletak pada pengatur lensa mengatur besarnya dioptri yang
diperlukan untk menyesuaikan focus sehingga detail fundus dapat terlihat jelas (bila
diperlukan).
d. Amati gambaran fundus yang terlihat.
Gambar. Fundus Normal
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 115
Buku Panduan CSL 2 2017
neovaskular
hemoragik
Gambar. Fundus Retinopati Diabetikum
Nervus III. Okulomotorius, Nervus IV. Troklearis, Nervus VI. Abdusen
1. Gerakan Okular Duksi (Monocular)
Gambar. Pemeriksaan N.III, N.IV, N.VI
a. Duduk berhadapan dengan pasien. Tutup salah satu mata pasien dengan menggunakan
telapak tangan pasien, kepala pasien tegak dan pengelihatan lurus ke depan. Gunakan
jari atau benda (misal: pena) sebagai target fiksasi tempatkan setinggi mata pasien pada
jarak 30 cm.
b. Minta pasien untuk mengikuti arah jari atau benda target fiksasi, pemeriksa menggerakan
jari atau benda target fiksasi sesuai enam lapang cardinal.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 116
Buku Panduan CSL 2 2017
c. Ulangi prosedur untuk mata sebelahnya.
2. Gerakan Okular Versi (Binocular)
a. Duduk berhadapan dengan pasien, kepala pasien tegak dan pengelihatan kedua mata
lurus ke depan. Gunakan jari atau benda (misal: pena) sebagai target fiksasi tempatkan
setinggi mata pasien pada jarak 30 cm.
b. Minta pasien untuk mengikuti arah jari atau benda target fiksasi, pemeriksa menggerakan
jari atau benda target fiksasi sesuai enam lapang cardinal dan gerakan ke atas dan ke
bawah pada garis tengah.
3. Reflek Pupil
Gambar. Pemeriksaan Reflek Pupil
a. Kondisikan kamar pemeriksaan pada keadaan temaram, minta pasien untuk melihat
benda yang jauh untuk fiksasi
b. Sinari mata kanan secara langsung dengan menggunakan pen-light dari arah samping
atau bawah.
c. Catat respon pupil langsung (direct pupil reflex)
d. Ulangi prosedur 1-3 untuk mata kiri.
e. Ulangi langkah 1 dan 2 pada mata kanan, amati respon pada mata kiri yang tidak disinari
(indirect pupil reflex). Kecepatan respon dan ukuran pupil normalnya akan ekuivalen
dengan respon pupil langsung.
f. Ulangi langkah 1,2, dan 5 pada mata kiri.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 117
Buku Panduan CSL 2 2017
Nervus V. Trigeminus
1. Uji Sentuhan Ringan dan Nyeri Wajah
Gambar. Pemeriksaan Sensoris Wajah
a. Pasien diminta untuk menutup mata, dan memberikan respon pada sentuhan daerah
wajah.
b. Pemeriksaan sensasi sentuhan ringan menggunakan kapas untuk memberikan usapan
pada satu sisi dahi, setelahnya lakukan hal yang sama pada posisi yang sama pada dahi
sisi yang lain.
c. Lakukan langkah 2 pada daerah pipi, dan rahang.
d. Periksa respon pasien, apakah respon pasien sama pada kedua sisi wajah.
e. Lakukan hal yang sama pada pemeriksaan uji nyeri dan tumpul, pemeriksaan dilakukan
dengan menggunakan pin tajam dan benda tumpul yang dilakukan dengan tekanan ringan
pada daerah wajah secara bergantian tajam dan tumpul dan pada kedua sisi wajah, minta
pasien menyebutkan sensasi yang dirasakan apakah tajam atau tumpul dan apakah
sensasi yang dirasakan simetris pada kedua sisi wajah.
2. Raba Kontraksi Otot Temporalis dan Maseter
a. Pemeriksa menempatkan jari-jari kedua tangannya pada otot temporalis pasien.
b. Pasien diminta untuk mengatupkan giginya (menggigit), rasakan kontraksi otot temporalis
pada tangan.
c. Lakukan hal yang sama pada pemeriksaan otot maseter.
3. Kontraksi Otot Pterygoideus anterior dan lateral
a. Uji gigit spatel
• Pasien diminta untuk menggigit spatel kayu/stainless steel.
• Pasien diminta untuk tetap menahan gigitannya, sementara pemeriksa menarik spatel.
• Nilai kekuatan otot pterygoideus medialnya.
b. Pergerakan Rahang Sisi ke Sisi
• Pemeriksa menempatkan jari-jari kedua tangannya pada rahang bawah pasien.
• Pasien diminta untuk menggerakkan rahang bawahnya ke arah kanan dan ke kiri. Nilai
apakah kekuatan otot pterigoideus lateral kanan dan kiri equivalen.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 118
Buku Panduan CSL 2 2017
• Jari pemeriksa memberikan tahanan pada rahang bawah pasien, dan minta pasien
untuk menggerakkan rahang bawah ke kanan dan ke kiri sesuai dengan arah tahanan
pemeriksa. Nilai apakah kekuatan otot pterigoideus lateral kanan dan kiri equivalen.
4. Reflek Sentakan Rahang
a. Pemeriksa duduk berhadapan dengan pasien.
b. Pasien diminta untuk membuka sedikit mulutnya.
c. Tempatkan ibu jari atau jari telunjuk pemeriksa pada anterior rahang bawah (dagu).
Pukulkan palu reflek pada ibu jari pemeriksa.
d. Reflek normal akan memberikan sedikit gerakan rahang bawah ke arah atas. Respon
abnormal akan memberikan sentakan yang berlebih.
Gambar. Pemeriksaan Reflek Sentakan Rahang
5. Reflek Kornea
Gambar. Pemeriksaan Reflek Kornea
Refleks ini dilakukan dengan menggunakan kapas yang diusapkan ringan pada kornea
a. Pemeriksa menggunakan kapas yang dibentuk meruncing.
b. Pasien diminta untuk melirik ke arah atas dan ujung runcing kapas ditempatkan dari sisi
lateral mata dan usapkan secara ringan pada kornea.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 119
Buku Panduan CSL 2 2017
c. Usapan pada kornea akan menyebabkan refleks menutup mata pada kedua mata.
Bandingkan respon reflek kornea pada kedua bola mata.
Nervus VII. Fasialis
1. Tes Fungsi Motorik Otot Fasial Bawah
Gambar. Pemeriksaan Motorik Otot Fasial Bawah
a. Pasien diminta untuk tersenyum dan memperlihatkan gigi-geliginya.
b. Pada respon yang normal sudut bibir simetris. Pada keadaan abnormal respon mulut
deviasi ke arah yang sehat.
2. Tes Fungsi Motorik Otot Fasial Atas
Gambar. Pemeriksaan Motorik Otot Fasial Atas
a. Pasien diminta untuk menutup kedua matanya kuat-kuat.
b. Pemeriksa mencoba untuk membuka kedua kelopak mata.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 120
Buku Panduan CSL 2 2017
c. Pada respon yang normal, kedua mata pasien tidak akan terbuka walaupun pemeriksa
berusaha membuka kedua kelopak mata dengan tenaga.
d. Minta pasien untuk mengangkat kedua alis.
e. Pada respon normal, akan tampak kerut pada kedua sisi dahi simetris. Pada respon
abnormal tak tampak adanya kerut dahi pada sisi yang sakit.
3. Tes Pengecap 2/3 anterior lidah
a. Test dilakukan dengan menggunakan 4 substansi rasa : manis (gula), asin (garam), pahit
(kina/kopi), asam (cuka). Semua subtansi disediakan dalam bentuk cairan.
b. Pasien diminta untuk menjulurkan lidahnya.
c. Pemeriksa meneteskan sampel pada lidah pasien dengan menggunakan pipet.
d. Pasien memberikan respon rasa sesuai dengan respon rasa yang dirasakan pasien.
Nervus VIII. Akustikus
Gambar. Pemeriksaan Rinne dan Webber
1. Uji Rinne
Tujuan melakukan tes Rinne adalah untuk membandingkan atara hantaran tulang dengan
hantaran udara pada satu telinga pasien.
a. Pemeriksa menggunakan garpu tala 512 Hz.
b. Pemeriksa membunyikan garpu tala secara lunak lalu menempatkan tangkainya tegak
lurus pada planum mastoid kanan pasien (belakang meatus akustikus eksternus).
c. Setelah pasien tidak mendengar bunyinya, segera garpu tala kita pindahkan di depan
meatus akustikus eksternus kanan pasien.
d. Lakukan hal yang sama pada telinga kiri.
e. Tes Rinne positif jika pasien masih dapat mendengarnya. Sebaliknya tes rinne negatif jika
pasien tidak dapat mendengarnya
2. Uji Weber
Tujuan kita melakukan tes weber adalah untuk membandingkan hantaran tulang antara
kedua telinga pasien.
a. Pemeriksa menggunakan garpu tala 512 Hz.
b. Pemeriksa membunyikan garpu tala secara lunak, lalu tangkainya kita letakkan tegak
lurus pada dahi tepat di garis tengah.
c. Minta pasien merespon adakah telinga yang mendengar lebih, ataukah sama keras.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 121
Buku Panduan CSL 2 2017
d. Jika telinga pasien mendengar lebih keras pada satu telinga maka terjadi lateralisasi ke
sisi telinga tersebut. Jika kedua pasien sama-sama tidak mendengar atau sama-sama
mendengar berarti tidak ada lateralisasi.
Nervus IX. Glossopharingeal
Gambar. Pemeriksaan N.IX
1. Reflek Muntah
a. Pasien diminta untuk membuka mulutnya lebar-lebar
b. Pemeriksa memberikan stimulus pada dinding faring dengan spatel lidah.
c. Periksa respon muntah
2. Test pengecap 1/3 posterior lidah
Pemeriksaan pengecap sama seperti pemeriksaan Nervus Fascialis hanya posisi
pemeriksaan pada 1/3 posterior lidah.
Nervus X. Vagus
1. Perubahan Bicara
a. Pasien diminta untuk berbicara kata atau satu kalimat.
b. Pemeriksa memeriksa bicara pasien, apakah ada disfoni atau disartria.
(Disfoni : kesulitan untuk menghasilkan suara karena paralisis pita suara (laring), suara
menjadi kasar dan volume suara berkurang. Disartria adalah kesulitan menghasilkan
artikulasi karena paralisis vagal sehingga menyebabkan kelemahan kontraksi soft
palatum.
2. Kontraksi Soft Palatum
a. Pasien diminta untuk membuka mulut dan berkata “Aaaaa”.
b. Pemeriksa memeriksa kontraksi soft palatum pada kedua sisi sekaligus memeriksa posisi
uvula.
c. Pada respon normal soft palatum (arkus palatum) kedua sisi terangkat simetris dan uvula
tetap pada posisi tengah.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 122
Buku Panduan CSL 2 2017
d. Respon abnormal akan didapatkan bila salah satu sisi soft palatum tidak terangkat, dan
uvula akan tertarik ke sisi yang berlawanan (sisi yang sehat).
3. Menelan
a. Pasien diminta untuk untuk menelan makanan kecil/air.
b. Pemeriksa memeriksa adakah kesulitan dalam menelan, atau adakah pasien tersedak.
Nervus XI. Accessory
1. Pemeriksaan Otot Sternocleidomastoideus
Gambar. Pemeriksaan Otot Sternocleidomastoideus
a. Pemeriksa meletakkan tangan pada pipi pasien.
b. Minta pasien untuk menoleh ke kanan dan ke kiri melawan tahanan tangan pemeriksa
2. Pemeriksaan Otot Trapezius
Gambar. Pemeriksaan Otot Trapezius
a. Pemeriksa berhadapan dengan pasien.
b. Pemeriksa meletakkan kedua tangan pada bahu pasien.
c. Minta pasien untuk mengangkat kedua bahu melawan tahanan tangan pasien.
d. Pemeriksa menilai kesimetrisan kontraksi kedua otot trapezius pasien.
Nervus. XII. Hypoglossal
Pemeriksaan Motoris Lidah
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 123
Buku Panduan CSL 2 2017
Gambar. Pemeriksaan N.XII
1. Pasien diminta untuk membuka mulut dan lidah tetap berada pada dasar mulut.
2. Pemeriksa memeriksa lidah pasien adakah fasikulasi dan atau atropi.
3. Pasien diminta untuk menjulurkan lidah.
4. Periksa adakah deviasi lidah. Paralisis lidah akan menyebabkan deviasi pada sisi yang
terkena (sisi yang sakit).
4. Item Profesionalisme
1. Percaya diri, minimal error.
2. Penalaran klinik baik dan bersesuaian dengan kasus.
3. Memperhatikan aspek kerahasiaan & etika pemeriksaan kepada pasien.
4. Cuci tangan WHO
G. DAFTAR PUSTAKA
1. Snell, Richard S, 2006, Anatomi Klinik Untuk Mahasiswa Kedokteran, edisi 6, EGC. Jakarta.
2. Szilagy, Peter G. , 2002 , Bate's guide to physical examination, McGraw – Hill , Chapter 5: 155-
208
3. http://www.osceskills.com/e-learning/modules/neurology/
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 124
Buku Panduan CSL 2 2017
CHECK LIST LATIHAN PEMERIKSAAN SARAF KRANIAL
No. Aspek Feedback
INTERPERSONAL
1. Membina sambung rasa
Salam, senyum, sapa memperkenalkan diri
2. Menjelaskan tujuan pemeriksaan
3. Memberikan instruksi penderita untuk duduk tegak
4. Cuci tangan WHO
CONTENT
Inspeksi
5. General assessment (laporkan hasil Inspeksi)
Pemeriksaan Saraf Kranialis
N. I. Olfaktorius
6. Pasien diperkenalkan dengan ketiga sampel tes dengan cara
menghidu terlebih dahulu
7. Pasien diminta untuk menutup mata, kemudian bernafas dengan
satu lubang hidung ditutup (alternatif: dengan menggunakan tangan
pasien).
8. Pemeriksa mendekatkan sampel tes ke hidung pasien yang tidak
ditutup. Sampel tes sebaiknya tidak mengiritasi, seperti tembakau,
teh, atau kopi.
9. Setiap lubang hidung dites bergantian.
10. Pemeriksa meminta pasien untuk melakukan inhalasi yang cukup,
lalu meminta pasien untuk mengidentifikasi sampel tes.
N. II. Optikus
A. Kaji Tajam Penglihatan
11. Posisikan pasien pada jarak 20 kaki (6 meter) dari Snellen chart
(untuk pemeriksaan visus dasar, Jika pasien memakai kacamata
sebagai alat bantu pengelihatan, maka pasien diminta melepas).
12. Pemeriksaan dilakukan pada mata kanan terlebih dahulu, mata kiri
ditutup dengan penutup mata (alternatif: pasien diminta untuk
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 125
Buku Panduan CSL 2 2017
menutup mata dengan tangannya).
13. Minta pasien untuk membacakan baris huruf hingga baris huruf
terkecil yang masih bisa dibaca.
14 Catat hasil pengukuran tajam pengelihatan dalam bentuk pecahan
(misal : 20/20)
• Apabila dalam satu baris, pasien bisa menyebutkan lebih dari ½
baris yang benar dan terdapat beberapa huruf yang salah maka
ditulis dengan 20/20 false x (x = berapa huruf yang salah)
• Apabila dalam satu baris, pasien bisa menyebutkan kurang dari ½
baris yang benar maka ditulis dengan 20/20 true x (x = berapa
huruf yang benar)
15. Ulangi prosedur untuk pemeriksaan mata kiri.
16. Jika pasien tidak dapat melihat huruf terbesar pada Snellen chart,
maka lakukan prosedur berikut:
Pemeriksa mengangkat satu tangannya dan ekstensikan dua atau
lebih jari, minta pasien untuk menghitung jari pemeriksa.
Bila pasien tidak dapat melihat jari pemeriksa pada jarak 6 m, maju
1 m, dan seterusnya.
Catat pada jarak berapa pasien dapat menghitung jari pemeriksa.
17. Jika pasien tidak dapat menghitung jari pemeriksa pada jarak 1 m,
periksa apakah pasien dapat melihat gerakan/lambaian dan dapat
menentukan arah gerakan/lambaian (kiri-kanan/atas-bawah)
18. Jika pasien tidak dapat melihat gerakan tangan, gunakan pen-light
untuk memeriksa apakah pasien dapat melihat cahaya. Catat respon
pasien terhadap cahaya : persepsi cahaya, persepsi arah cahaya,
persepsi tanpa cahaya.
B. Lapang Pandang (Konfrontasi)
18. Mintalah pasien duduk dihadapan petugas pada jarak jangkauan
tangan ( 30 – 50 cm ).
19. Minta pasien untuk menutup mata kiri dengan tangan kirinya.
20. Pemeriksa menutup mata di sisi yang sama dengan mata pasien
yang ditutup
21. Minta pasien untuk menatap tepat pada hidung pemeriksa (fiksasi).
22. Mintalah pasien agar memberi respon bila melihat objek (jari/pena)
yang digerakkan petugas di mana mata tetap terfiksasi dengan mata
pemeriksa.
23. Gerakkan obyek (dapat berupa jari pemeriksa atau pena) dari perifer
ke tengah di mulai dari arah superior, superior temporal, temporal,
temporal inferior, inferior, inferior nasal, superior nasal.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 126
Buku Panduan CSL 2 2017
24. Ulangi langkah tersebut pada pemeriksaan mata kiri.
C. Funduskopi
25. Pasien posisi duduk. Pemeriksa memegang oftalmoskop dengan
tangan kanan untuk memeriksa mata kiri pasien dan tangan kiri
dengan, pemeriksa memposisikan jari telunjuk pada pengatur lensa.
26. Menyalakan oftalmoskop, memegang dengan menempel pada mata
pasien. Lalu perlahan bergerak maju mendekati pasien dengan
oftalmoskop diposisikan pada sisi temporal pasien hingga gambaran
fundus terlihat.
27. Jari telunjuk yang terletak pada pengatur lensa mengatur besarnya
dioptri yang diperlukan untk menyesuaikan focus sehingga detail
fundus dapat terlihat jelas (bila diperlukan).
28. Amati gambaran fundus yang terlihat
N.III. Okulomotorius, N.IV. Troklearis, N.VI. Abdusen
A. Gerakan Okular Duksi (Monocular)
29. Duduk berhadapan dengan pasien. Tutup mata kiri pasien dengan
menggunakan telapak tangan pasien, kepala pasien tegak dan
pengelihatan lurus ke depan. Gunakan jari atau benda (misal: pena)
sebagai target fiksasi tempatkan setinggi mata pasien pada jarak 30
cm.
30. Minta pasien untuk mengikuti arah jari atau benda target fiksasi,
pemeriksa menggerakan jari atau benda target fiksasi sesuai enam
lapang cardinal.
31. Ulangi Prosedur untuk mata kiri.
B. Gerakan Okular Versi (Binocular)
32. Duduk berhadapan dengan pasien, kepala pasien tegak dan
pengelihatan lurus ke depan. Gunakan jari atau benda (misal: pena)
sebagai target fiksasi tempatkan setinggi mata pasien pada jarak 30
cm.
33. Minta pasien untuk mengikuti arah jari atau benda target fiksasi,
pemeriksa menggerakan jari atau benda target fiksasi sesuai enam
lapang cardinal dan gerakan ke atas dan ke bawah pada garis
tengah.
D. Reflek Pupil
35. Kondisikan kamar pemeriksaan pada keadaan temaram, minta
pasien untuk melihat benda yang jauh untuk fiksasi.
36. Sinari mata kanan secara langsung dengan menggunakan pen-light
dari arah samping atau bawah.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 127
Buku Panduan CSL 2 2017
37. Catat respon pupil langsung (direct pupil reflex)
38. Ulangi prosedur 1-3 untuk mata kiri.
39. Ulangi langkah 1 dan 2 pada mata kanan, amati respon pada mata
kiri yang tidak disinari (indirect pupil reflex). Kecepatan respon dan
ukuran pupil normalnya akan ekuivalen dengan respon pupil
langsung.
40. Ulangi langkah 1,2, dan 5 pada mata kiri.
Nervus V. Trigeminus
A. Uji Sentuhan Ringan dan Nyeri Wajah
41. Pasien diminta untuk menutup mata, dan memberikan respon pada
sentuhan daerah wajah.
42. Pemeriksaan sensasi sentuhan ringan menggunakan kapas untuk
memberikan usapan pada satu sisi dahi, setelahnya lakukan hal
yang sama pada posisi yang sama pada dahi sisi yang lain.
43. Lakukan langkah 2 pada daerah pipi, dan rahang.
44. Periksa respon pasien, apakah respon pasien sama pada kedua sisi
wajah.
45. Lakukan hal yang sama pada pemeriksaan uji nyeri, pemeriksaan uji
nyeri dilakukan dengan menggunakan pin tajam yang dilakukan
dengan tekanan ringan pada daerah wajah.
B. Raba Kontraksi Otot Temporalis dan Maseter
46. Pemeriksa menempatkan jari-jari kedua tangannya pada otot
temporalis pasien.
47. Pasien diminta untuk mengatupkan giginya (menggigit), rasakan
kontraksi otot temporalis pada tangan.
48. Lakukan hal yang sama pada pemeriksaan otot maseter.
C. Kekuatan otot Pterygoideus Medial dan Lateral
49. Pasien diminta untuk menggigit spatel dengan kuat, kemudian
pemeriksa menarik spatel. Nilai kekuatan otot pterygoideus medial
50. Pemeriksa menempatkan jari-jari kedua tangannya pada rahang
bawah pasien Pasien diminta untuk menggerakkan rahang
bawahnya ke kanan dan ke kiri. Nilai apakah kekuatan otot
pterigoideus lateral kanan dan kiri equivalen.
51. Jari pemeriksa memberikan tahanan pada rahang bawah pasien,
dan minta pasien untuk menggerakkan rahang bawah ke kanan dan
ke kiri sesuai dengan arah tahanan pemeriksa. Nilai apakah
kekuatan otot pterigoideus lateral kanan dan kiri equivalen.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 128
Buku Panduan CSL 2 2017
D. Reflek Sentakan Rahang
52. Pemeriksa duduk berhadapan dengan pasien.
53. Pasien diminta untuk membuka sedikit mulutnya.
54. Tempatkan ibu jari atau jari telunjuk pemeriksa pada anterior rahang
bawah (dagu). Pukulkan palu reflek pada ibu jari pemeriksa.
55. Periksa respon pasien.
E. Reflek Kornea
56. Pemeriksa menggunakan kapas yang dibentuk meruncing.
57. Pasien diminta untuk melirik ke arah atas dan ujung runcing kapas
ditempatkan dari sisi lateral mata dan usapkan secara ringan pada
kornea.
58. Usapan pada kornea akan menyebabkan refleks menutup mata
pada kedua mata. Bandingkan respon reflek kornea pada kedua
bola mata.
N.VII. Fasialis
A. Tes Fungsi Motorik Otot Wajah Bawah
59. Pasien diminta untuk tersenyum dan memperlihatkan gigi-geliginya.
B. Tes Fungsi Motorik Otot Wajah Atas
60. Pasien diminta untuk menutup kedua matanya kuat-kuat.
61. Pemeriksa mencoba untuk membuka kedua kelopak mata.
62. Minta pasien untuk mengangkat kedua alis.
C. Tes Pengecap 2/3 anterior lidah
63 Test dilakukan dengan menggunakan 4 substansi rasa : manis
(gula), asin (garam), pahit (kina), asam (cuka). Semua subtansi
disediakan dalam bentuk cairan.
64. Pasien diminta untuk menjulurkan lidahnya.
65. Pemeriksa meneteskan sampel pada lidah pasien dengan
menggunakan pipet.
66. Pasien memberikan respon rasa sesuai dengan respon rasa yang
dirasakan pasien.
N.VIII. Akustikus
A. Tes Rinne
67. Pemeriksa menggunakan garpu tala 512 Hz.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 129
Buku Panduan CSL 2 2017
68. Pemeriksa membunyikan garpu tala secara lunak lalu menempatkan
tangkainya tegak lurus pada planum mastoid kanan pasien
(belakang meatus akustikus eksternus).
69. Setelah pasien tidak mendengar bunyinya, segera garpu tala kita
pindahkan di depan meatus akustikus eksternus kanan pasien.
70. Lakukan hal yang sama pada telinga kiri.
B. Tes Weber
71. Pemeriksa menggunakan garpu tala 512 Hz
72. Pemeriksa membunyikan garpu tala secara lunak, lalu tangkainya
kita letakkan tegak lurus pada dahi tepat di garis tengah.
73. Minta pasien merespon adakah telinga yang mendengar lebih,
ataukah sama keras.
N. IX. Glossopharingeal
A. Reflek Muntah (Gag Reflex)
74. Pasien diminta untuk membuka mulutnya lebar-lebar
75. Pemeriksa memberikan stimulus pada dinding faring dengan spatel
lidah.
76. Periksa respon muntah
B. Tes Pengecap 1/3 Posterior Lidah
77. Pemeriksaan pengecap sama seperti pemeriksaan Nervus Fascialis
hanya posisi pemeriksaan pada 1/3 posterior lidah.
N. X. Vagus
A. Perubahan Bicara
78. Pasien diminta untuk berbicara satu kata atau satu kalimat.
79. Pemeriksa memeriksa bicara pasien, apakah ada disfoni atau
disartria.
B. Kontraksi Soft Palatum
80. Pasien diminta untuk membuka mulut dan berkata “Aaaaa”
81. Pemeriksa memeriksa kontraksi soft palatum pada kedua sisi
sekaligus memeriksa posisi uvula.
C. Menelan
82. Pasien diminta untuk untuk menelan makanan kecil/air.
83. Pemeriksa memeriksa adakah kesulitan dalam menelan, atau
adakah pasien tersedak.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 130
Buku Panduan CSL 2 2017
N. XI. Accessory
A. Pemeriksaan Otot Sternocleidomastoideus
84. Pemeriksa meletakkan tangan pada pipi pasien.
85. Minta pasien untuk menoleh ke kanan dan ke kiri melawan tahanan
tangan pemeriksa.
B. Pemeriksaan Otot Trapezius
86. Pemeriksa berhadapan dengan pasien
87. Pemeriksa meletakkan kedua tangan pada bahu pasien.
88. Minta pasien untuk mengangkat kedua bahu melawan tahanan
tangan pasien.
89. Pemeriksa menilai kesimetrisan kontraksi kedua otot trapezius
pasien.
N. XII. Hypoglossal
90. Pasien diminta untuk membuka mulut dan lidah tetap berada pada
dasar mulut.
91. Pemeriksa memeriksa lidah pasien adakah fasikulasi atau atropi.
92. Pasien diminta untuk menjulurkan lidah
93. Periksa adakah deviasi lidah
PROFESIONALISME
95. Melakukan dengan penuh percaya diri, serta minimal error
96. Penalaran klinik baik dan bersesuaian dengan kasus
97. Memperhatikan aspek kerahasiaan & etika pemeriksaan kepada
pasien
98. Cuci tangan WHO
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 131
Buku Panduan CSL 2 2017
PEMERIKSAAN MOTORIS
A. TEMA
Pemeriksaan motoris dan kekuatan otot
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Mampu melakukan pemeriksaan sensoris dan kekuatan otot
2. Mampu menjelaskan tujuan dan interpretasi hasil pemeriksaan sensoris dan kekuatan otot
3. Mampu memilih metode untuk pemeriksaan
4. Mampu melakukan penalaran klinik terhadap hasil pemeriksaan
C. ALAT DAN BAHAN
Meja dan Bed pemeriksaan
D. SKENARIO
GENERAL WEAKNESS
Seorang laki-laki datang kepada saudara dengan keluhan badan terasa lemah. kedua tangan dan
kaki lemah untuk digerakkan. Anda kemudian melakukan pemeriksaan motoris dan kekuatan otot
pada pasien ini.
E. DASAR TEORI
1. Tonus Otot dan Kekuatan Otot
Pada pemeriksaan otot dinilai tonus otot dan kekuatan otot.
• Tonus otot: pada otot normal dengan inervasi intak sedang berelaksasi, otot tersebut masih
mempunyai tegangan residu yang kita kenal dengan tonus otot. Tonus otot dapat diperiksa
dengan meraba dan merasakan resistansi otot setelah dilakukan peregangan pasif (gerakan
pasif).
Contoh pemeriksaan tonus otot pada tangan:
Minta pasien untuk bersikap relaks, kemudian pemeriksa mengambil salah satu tangan
pasien, fleksi dan ekstensikan siku. Pemeriksa memperhatikan resistensi otot. Evaluasi
apakah tonus otot normal, rigid atau flaccid. Rigidity jika ketika pemeriksa menggerakkan
lengan ke depan dan belakang terdapat tahanan tersentak-sentak. Flaccidity, jika ketika
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 132
Buku Panduan CSL 2 2017
pemeriksa menggerakan lengan ke depan dan belakang, tidak terdapat tahanan,hampir
seperti terkulai.
• Pemeriksaan kekuatan otot dilakukan dengan menyuruh pasien melakukan gerakan aktif
melawan tahanan pemeriksa. Jika otot yang akan diperiksa terlalu lemah, minta pasien untuk
menggerakkan otot melawan gravitasi. Pengurangan kekuatan otot disebut parese dan
kehilangan seluruh kekuatan otot disebut plegia.
Penilaian kekuatan otot digradasikan dalam skala 0-5
0 Tidak ada kontraksi otot
1 Ditemukan kedutan otot minimal
2 Pergerakan aktif dari bagian tubuh melawan gravitasi yang terbatas
3 Pergerakan aktif melawan gravitasi
4 Pergerakan aktif melawan gravitasi dan sedikit tahanan
5 Pergerakan aktif melawan tahanan
F. PROSEDUR
Pemeriksaan Kekuatan Otot
1. Test flexion (C5, C6—biceps)
• Minta pasien untuk menekukkan lengannya pada siku
• Pemeriksa menempatkan salah satu tangannya pada otot biseps pasien dan tangan yang
lainnya pada pergelangan tangan pasien, beri tahanan
• Minta pasien untuk melawan tahanan yang diberikan oleh pemeriksa dengan berupaya
menekukkan lengannya.
Gambar. Tes Fleksi
2. Test ekstensi (C6, C7, C8—triceps)
• Minta pasien untuk menekukkan lengannya pada siku
• Pemeriksa menempatkan tangannya pada pergelangan tangan pasien, beri tahanan
• Minta pasien untuk melawan tahanan yang diberikan oleh pemeriksa dengan berupaya
meluruskan lengannya.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 133
Buku Panduan CSL 2 2017
Gambar. Tes Ekstensi
3. Test ekstensi pada pergelangan tangan (C6, C7,C8, radial nerve)
• Minta pasien untuk meluruskan lengannya dan menggengam
• Tempatkan tangan pemeriksa pada genggaman pasien dan memberi tahanan berupa upaya
menarik genggaman pasien ke arah bawah
• Minta pasien untuk melawan tahanan tersebut
Gambar. Ekstensi Pergelangan Tangan
4. Test the grip atau tes genggam (C7, C8, T1).
• Tempatkan jari telunjuk dan jari tengah pemeriksa pada telapak tangan pasien
• Minta pasien untuk menggenggam jari pemeriksa tersebut dengan kuat
• Pemeriksa mengusahakan menarik jari tersebut dari genggaman pasien
Gambar. Test The Grip atau Tes Genggam
5. Test finger abduction (C8, T1, n. ulnaris).
• Posisikan tangan pasien dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan jari jari memekar
• Minta pasien untuk mempertahankan posisi tersebut
• Pemeriksa berusaha merapatkan jari-jari pasien.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 134
Buku Panduan CSL 2 2017
Gambar. Test Finger Abduction
6. Test opposition of the thumb (C8, T1, n. medianus).
• Tempatkan tangan pemeriksa seperti pada gambar, beri tahanan
• Minta pasien untuk menyentuh ujung jari kelingkingnya dengan ibu jari dengan melawan
tahanan pemeriksa.
Gambar. Test Opposition of the Thumb
7. Test flexion at the hip (L2, L3, L4—iliopsoas)
• Tempatkan tangan pemeriksa di atas lutut pasien, beri tahanan
• Minta pasien untuk mengangkat kakinya melawan tahanan pemeriksa.
Gambar. Test Flexion at the Hip
8. Test extension at the knee (L2, L3, L4—quadriceps)
• Pemeriksa menopang lutut pasien pada posisi fleksi, pegang pergelangan kaki pasien, beri
tahanan.
• Minta pasien untuk meluruskan kakinya melawan tahanan pemeriksa.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 135
Buku Panduan CSL 2 2017
Gambar. Test Extension at the Knee
9. Test flexion at the knee (L4, L5, S1, S2—hamstrings)
• Minta pasien untuk memposisikan kakinya fleksi pada lutut
• Instruksikan pasien untuk menahan usaha pemeriksa untuk meluruskan kakinya.
Gambar. Test Flexion at the Knee
10. Test dorsiflexion (terutama L4, L5) dan plantar flexion (terutama S1)
• Minta pasien untuk melawan tahanan pemeriksa dengan mendorong telapak kaki ke arah
atas
Gambar. Test Dorsiflexion
• Minta pasien untuk melawan tahanan pemeriksa dengan mendorong telapak kaki ke arah
bawah
Gambar. Test Plantarflexion
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 136
Buku Panduan CSL 2 2017
G. DAFTAR PUSTAKA
1. Bahan kuliah Neurologi FK UNSRI, 2000
2. Bahan kuliah Neurologi FK UI, 2010
3. Panduan CSL Pemeriksaan Neuropsikiatri Unhas, 2010
4. Swartz, M.H., 1995. Buku Ajar Diagnostik Fisik. Jakarta: EGC
5. Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Jakarta: 2006
6. Lynn S. Bickley: Bate's guide to physical examination.
7. Swartz: Textbook of physical diagnosis. Ed 5. Elsevier.2007
8. Afzal Mir: Atlas of clinical diagnosis. Ed 2. Elshevier science limited. 2003
9. Burnside-Mc Glynn: Adams Diagnosis Fisik. Edisi 17. EGC. Jakarta: 1995
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 137
Buku Panduan CSL 2 2017
CEKLIST KETERAMPILAN PEMERIKSAAN SISTEM MOTORIS
No Prosedur Feedback
INTERAKSI DOKTER – PASIEN
1.
Senyum, salam, sapa
2. Beritahukan kepada pasien mengenai tindakan yang akan
dilakukan dan persetujuan tindakan (informed consent)
PEMERIKSAAN KEKUATAN OTOT
3. Lakukan pemeriksaan test flexion (C5, C6—biceps) :
• Meminta pasien untuk menekukkan lengannya pada siku
• Tempatkan salah satu tangan pemeriksa pada otot biseps
pasien dan tangan yang lainnya pada pergelangan tangan
pasien, beri tahanan
• Instruksikan pasien untuk melawan tahanan dengan berupaya
menekukkan lengannya.
4. Lakukan pemeriksaan test ekstensi (C6, C7, C8—triceps):
• Meminta pasien untuk menekukkan lengannya pada siku
• Tempatkan tangan pemeriksa pada pergelangan tangan pasien,
beri tahanan
• Instruksikan pasien untuk melawan tahanan dengan berupaya
meluruskan lengannya
5. Lakukan pemeriksaan test ekstensi pada pergelangan tangan
(C6, C7,C8, radial nerve):
• Meminta pasien untuk meluruskan lengannya dan menggengam
• Tempatkan tangan pemeriksa pada genggaman pasien dan
memberi tahanan berupa upaya menarik genggaman pasien ke
arah bawah
• Instruksikan pasien untuk melawan tahanan tersebut
6. Lakukan pemeriksaan test the grip atau tes genggam (C7, C8,
T1):
• Tempatkan jari telunjuk dan jari tengah pemeriksa pada telapak
tangan pasien
• Meminta pasien untuk menggenggam jari pemeriksa tersebut
dengan kuat
• Usahakan menarik jari tersebut dari genggaman pasien
7. Lakukan pemeriksaan test finger abduction (C8, T1, n.
ulnaris):
• Posisikan tangan pasien dengan telapak tangan menghadap ke
bawah dan jari jari memekar
• Instruksikan pasien untuk mempertahankan posisi tersebut
• Pemeriksa berusaha merapatkan jari-jari pasien
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 138
Buku Panduan CSL 2 2017
8. Lakukan pemeriksaan test opposition of the thumb (C8, T1, n.
medianus):
• Tempatkan tangan pemeriksa seperti pada gambar (baca
prosedur), beri tahanan
• Instruksikan pasien untuk menyentuh ujung jari kelingkingnya
dengan ibu jari dengan melawan tahanan pemeriksa
9. Lakukan pemeriksaan test flexion at the hip (L2, L3, L4—
iliopsoas):
• Tempatkan tangan pemeriksa di atas lutut pasien, beri tahanan
• Instruksikan pasien untuk mengangkat kakinya melawan tahanan
10 Lakukan pemeriksaan test extension at the knee (L2, L3, L4—
quadriceps):
• Topanglah lutut pasien pada posisi fleksi, pegang pergelangan
kaki pasien, beri tahanan.
• instruksikan pasien untuk meluruskan kakinya melawan tahanan
11 Lakukan pemeriksaan test flexion at the knee (L4, L5, S1, S2—
hamstrings) :
• Meminta pasien untuk memposisikan kakinya fleksi pada lutut
• Instruksikan pasien untuk menahan usaha pemeriksa untuk
meluruskan kakinya.
12 Lakukan pemeriksaan test dorsoflexion (terutama L4, L5)
• Instruksikan pasien untuk melawan tahanan pemeriksa dengan
mendorong telapak kaki ke arah atas
13 Lakukan pemeriksaan test plantar flexion (terutama S1):
• Instruksikan pasien untuk melawan tahanan pemeriksa dengan
mendorong telapak kaki ke arah bawah
PROFESIONALISME
14 Melakukan dengan penuh percaya diri
15
Melakukan dengan kesalahan minimal
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 139
Buku Panduan CSL 2 2017
TES FUNGSI SISTEM SENSORIS
dr. Rizki Hanriko, Sp.PA
A. TEMA
Keterampilan pemeriksaan fisik fungsi sistem sensoris
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
• Mampu melakukan pemeriksaan fungsi sistem sensoris
• Mampu memilih metode untuk pemeriksaan
• Mampu menjelaskan tujuan dan intrepretasi hasil pemeriksaan
• Mampu melakukan penalaran klinik terhadap hasil pemeriksaan
C. ALAT DAN BAHAN
• Kapas
• Peniti
• Garpu tala
• Pensil
• Koin 500
• Korek kuping
D. SKENARIO
POLINEUROPATI
Seorang laki-laki datang kepada saudara dengan keluhan sekujur tubuh sering gatal-gatal. Beberapa hari ini kaki dan
tangannya terasa kesemutan dan hilang rasa. Dari riwayat penyakit dahulu didapatkan bahwa pasien sering mengkonsumsi
alkohol dan pernah melakukan pemeriksaan laboratorium gula darah. Anda kemudian melakukan tes fungsi sensori pada
pasien ini.
E. DASAR TEORI
Untuk mengevaluasi sistem sensoris, ada beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan sesuai jalur yang terkena,
yaitu
1. Tes rasa nyeri dan suhu (traktus spinotalamicus)
2. Tes posisi dan vibrasi ( kolumna posterior)
3. Tes sentuhan halus ( kedua jalur)
4. Sensasi diskriminasi yang melibatkan korteks serebri.
Pada pasien tanpa gejala atau tanda kelainan neurologis, pemeriksaan
fungsi sensoris dapat dilakukan secara cepat pada distal jari tangan dan
kaki. Pemeriksa dapat memilih untuk melakukan tes sentuhan halus,
rasa nyeri dan vibrasi. Jika didapatkan hasil yang normal, maka sisa tes
yang lain tidak diperlukan. Akan tetapi jika didapatkan gejala atau tanda
yang menunjukkan adanya kelainan neurologis, pemeriksaan harus
dilakukan semua. Pemeriksaan harus membandingkan masing-masing
sisi, distal dan proksimal. Kelainan neurologis biasanya menimbulkan
defisit sensoris yang pertamakali terlihat di distal dibandingkan
proksimal.
Nervus medianus adalah saraf utama yang mempersarafi tangan,
karena mempersarafi permukaan palmar jari-jari tangan yang
merupakan bagian tangan yang umumnya digunakan untuk meraba.
Nervus ulnaris dan nervus radialis menyuplai sensasi pada permukaan
tangan seperti terlihat pada gambar di sebelah.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 140
Buku Panduan CSL 2 2017
F. PROSEDUR
1. Persiapan
✓ Persilahkan pasien untuk duduk di bed menghadap pemeriksa yang berada pada posisi berdiri.
✓ Apa yang akan dilakukan dan apa respon yang harus pasien lakukan.
✓ Selama tes mata pasien dalam posisi tertutup, kecuali saat tertentu kita pinta membuka mata.
2. Tes Sentuhan Halus
✓ Siapkan kapas kemudian sentuhkan secara halus kapas ke dorsum salah satu jari tangan dari distal
ke proksimal.
✓ Pinta pasien menyebutkan di mana posisi sensasi yang dirasakan
✓ Kemudian sentuhkan secara halus ujung kapas ke permukaan salah satu jari kaki dari distal ke
proksimal.
✓ Pinta pasien menyebutkan di mana posisi sensasi yang dirasakan
✓ Jika sensasi yang dirasakan normal, lanjutkan ke tes berikutnya.
✓ Jika sensasi tidak dirasakan, teruskan menyentuh ke arah proksimal sampai sensasi dirasakan. Catat
sampai dermatom mana sensasi tersebut mulai dirasakan.
3. Tes Rasa Nyeri
✓ Gunakan
benda tajam dan tumpul, kali
ini peniti
✓ Sentuhkan ujung tajam dan tumpul secara acak
pada punggung tangan secara halus, hindari melukai atau menyakiti pasien.
✓ Tanyakan apakah yang disentuhkan tajam atau tumpul. Orang normal bisa membedakan sensasi tajam-
tumpul. Bila tidak dapat membedakan, teruskan tes ke arah proksimal tangan.
✓ Lakukan pada kedua tangan.
✓ Lanjutkan tes ke punggung kaki kanan dan kiri.
✓ Jangan menggunakan peniti yang sama untuk orang lain.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 141
Buku Panduan CSL 2 2017
4. Tes Vibrasi
✓ Gunakan garpu tala 128 Hz, getarkan dengan memukulkannya ke tumit tangan.
✓ Letakkan garpu tala diatas sendi interfalanx distal jari telunjuk pasien.
✓ Tanyakan apa yang dirasakan pasien. Normal akan merasakan getaran, bila tidak teruskan tes ke sendi
yang lebih proksimal.
✓ Lakukan pada kedua tangan
✓ Kemudian getarkan lagi garpu tala, letakkan di atas sendi interfalanx distal jempol kaki.
✓ Tanyakan apa yang dirasakan pasien. Normal akan merasakan getaran, bila tidak teruskan tes ke sendi
yang lebih proksimal.
✓ Lakukan pada kedua kaki.
5. Tes
Posisi
✓ Pegang lateral palanx distal jari tengah tangan pasien
dengan jempol dan telunjuk tangan pemeriksa , jempol dan telunjuk tangan lain memegang palanx
intermedia.
✓ Gerakkan palanx distal pasien ke atas dan ke bawah sambil diberitahu kepada pasien bahwa ini ke atas,
ini ke bawah (mata pasien terbuka)
✓ Kemudian suruh pasien memejamkan mata kembali.
✓ Gerakkan palanx distal sambil tanyakan ke pasien kemana palanx tersebut kita gerakkan. Normal bisa
mengetahui kemana gerakan, bila tidak lanjutkan ke sendi yang lebih proksimal.
✓ Lakukan pada kedua tangan.
✓ Lanjutkan pada jempol kedua kaki.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 142
Buku Panduan CSL 2 2017
6. Tes sensasi diskriminatif
a. Stereognosis
✓ Letakkan objek yang sudah dikenal oleh pasien
seperti koin 500, peniti, pensil dan korek kuping.
✓ Taruh salah satu objek ke tangan pasien.
✓ Dengan mata terpejam minta pasien merasakan
objek, minta dia menyebutkan objek yang
dirasakan.
✓ Minta pasien menyebutkan dan menyebutkan bagian spesifik (misal, bagian angka dan bagian garuda
pada koin 500; kepala dan batang korek kuping, kepala dan ekor peniti dll)
b. Identifikasi Nomor
✓ Dalam keadaan mata tertutup, tuliskan dengan ujung pensil yang tumpul sebuah angka paada telapak
tangan pasien
✓ Minta pasien menyebutkan angka yang dituliskan. Normal bisa mengetahui angka yang dituliskan,
abnormal dapat diakibatkan motor impairment, arthritis dll.
c. Diskriminasi 2 titik
✓ Gunakan
2 peniti, pegang dengan rapat.
✓ Sentuhkan kedua ujung tajam peniti pada ujung jari jari tengah tangan pasien pada satu titik lokasi.
✓ Minta pasien menyebutkan apakah yang dirasakan satu atau dua titik sentuhan. Normal bisa
membedakan satu atau dua titik sentuhan. Bila tidak dapat dirasakan, perlebar jarak kedua titik sentuhan
sampai pasien bisa merasakan.
d. Titik Lokasi
✓ Sentuh pasien pada sembarang titik lokasi dengan telunjuk.
✓ Pinta pasien membuka mata dan menunjukkan di mana lokasi yang pemeriksa barusan sentuh.
✓ Pinta pasien memejamkan mata kembali.
✓ Kemudian sentuh pasien pada dua titik lokasi berbeda dan berlawanan secara bersamaan. Misalnya pada
pipi kiri dan lengan kanan.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 143
Buku Panduan CSL 2 2017
✓ Tanyakan kepada pasien di mana letak titik lokasi sentuhan.Orang normal dapat mengetahui posisi
sentuhan. Kelainan yang disebut extiction phenomenon, tidak dapat membedakan sisi mana yang
disentuh( misal, tidak mengetahui pipi kiri dan lengan kanan tapi pipi dan lengan kanan atau pipi dan
lengan kiri). Kelainan ini disebabkan gangguan pada lobus temporal.
G. DAFTAR PUSTAKA
✓ Lynn S. Bickley: Bate's guide to physical examination.
✓ Swartz: Textbook of physical diagnosis. Ed 5. Elsevier.2007
✓ Afzal Mir: Atlas of clinical diagnosis. Ed 2. Elshevier science limited. 2003
✓ Burnside-Mc Glynn: Adams Diagnosis Fisik. Edisi 17. EGC. Jakarta: 1995
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 144
Buku Panduan CSL 2 2017
H. CEKLIS LATIHAN
No Aspek Umpan
Balik
INTERPERSONAL
1 Membina sambung rasa
• Salam dan perkenalan diri.
• Sikap terbuka dan ramah.
• Kontak mata sewajarnya.
2 Persilahkan pasien untuk duduk di bed menghadap pemeriksa yang berada
pada posisi berdiri.
3 Jelaskan apa yang akan dilakukan dan apa respon yang harus pasien
lakukan.
Selama tes mata pasien dalam posisi tertutup, kecuali saat tertentu kita pinta
membuka mata.
CONTENT
Tes Sentuhan Halus
4 Siapkan kapas kemudian sentuhkan secara halus kapas ke dorsum satu jari
tangan dari distal ke proksimal.
5 Pinta pasien menyebutkan di mana posisi sensasi yang dirasakan
6 Kemudian sentuhkan secara halus ujung kapas ke permukaan salah satu jari
kaki dari distal ke proksimal.
7 Pinta pasien menyebutkan di mana posisi sensasi yang dirasakan
8 Jika sensasi yang dirasakan normal, lanjutkan ke tes berikutnya.
9 Jika sensasi tidak dirasakan, teruskan menyentuh ke arah proksimal sampai
sensasi dirasakan. Catat sampai dermatom mana sensasi tersebut mulai
dirasakan.
Tes Rasa Nyeri
10 Gunakan benda tajam dan tumpul, kali ini peniti.
Sentuhkan ujung tajam dan tumpul secara acak pada punggung tangan
secara halus, hindari melukai atau menyakiti pasien.
11 Tanyakan apakah yang disentuhkan tajam atau tumpul. Orang normal bisa
membedakan sensasi tajam-tumpul. Bila tidak dapat membedakan, teruskan
tes ke arah proksimal tangan.
12 Lakukan pada kedua tangan.
13 Lanjutkan tes ke punggung kaki kanan dan kiri.
Tes Vibrasi
14 Gunakan garpu tala 128 Hz, getarkan dengan memukulkannya ke tumit
tangan.
15 Letakkan garpu tala diatas sendi interfalanx distal jari telunjuk pasien.
16 Tanyakan apa yang dirasakan pasien. Normal akan merasakan getaran, bila
tidak teruskan tes ke sendi yang lebih proksimal.
17 Lakukan pada kedua tangan
18 Kemudian getarkan lagi garpu tala, letakkan di atas sendi interfalanx distal
jempol kaki.
19 Tanyakan apa yang dirasakan pasien. Normal akan merasakan getaran, bila
tidak teruskan tes ke sendi yang lebih proksimal.
20 Lakukan pada kedua kaki.
Tes Posisi
21 Pegang lateral palanx distal jari tengah tangan pasien dengan jempol dan
telunjuk tangan pemeriksa , jempol dan telunjuk tangan lain memegang palanx
intermedia.
22 Gerakkan palanx distal pasien ke atas dan ke bawah sambil diberitahu kepada
pasien bahwa ini ke atas, ini ke bawah (mata pasien terbuka)
23 Kemudian suruh pasien memejamkan mata kembali.
24 Gerakkan palanx distal sambil tanyakan ke pasien kemana palanx tersebut
kita gerakkan. Normal bisa mengetahui kemana gerakan, bila tidak lanjutkan
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 145
Buku Panduan CSL 2 2017
ke sendi yang lebih proksimal.
25 Lakukan pada kedua tangan.
26 Lanjutkan pada jempol kedua kaki.
Tes Sensasi Diskriminasi
Stereognosis
27 Letakkan objek yang sudah dikenal oleh pasien seperti koin 500, peniti, pensil
dan korek kuping.
Taruh salah satu objek ke tangan pasien.
28 Dengan mata terpejam minta pasien merasakan objek, minta dia menyebutkan
objek yang dirasakan.
29 Minta pasien menyebutkan dan menyebutkan bagian spesifik (misal, bagian
angka dan bagian garuda pada koin 500; kepala dan batang korek kuping,
kepala dan ekor peniti dll)
Identifikasi Nomor
30 Dalam keadaan mata tertutup, tuliskan dengan ujung pensil yang tumpul
sebuah angka paada telapak tangan pasien
31 Minta pasien menyebutkan angka yang dituliskan.
Diskriminasi 2 titik
32 Gunakan 2 peniti, pegang dengan rapat.
Sentuhkan kedua ujung tajam peniti pada ujung jari jari tengah tangan pasien
pada satu titik lokasi.
33 Minta pasien menyebutkan apakah yang dirasakan satu atau dua titik
sentuhan. Perlebar jarak kedua titik sentuhan sampai pasien bisa merasakan.
Posisi
34 Sentuh pasien pada sembarang lokasi dengan telunjuk.
35 Pinta pasien membuka mata dan menunjukkan di mana lokasi yang pemeriksa
barusan sentuh.
36 Pinta pasien memejamkan mata kembali.
37 Sentuh pasien pada dua lokasi berbeda dan berlawanan secara bersamaan.
Misalnya pada pipi kiri dan lengan kanan.
38 Tanyakan kepada pasien di mana letak sentuhan.
PROFESSIONALISM
39 Melakukan dengan penuh percaya diri
40 Melakukan dengan kesalahan minimal
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 146
Buku Panduan CSL 2 2017
PEMERIKSAAN MUSKULOSKELETAL DAN
RANGE OF MOTION (ROM)
H. TEMA
Keterampilan Klinis Pemeriksaan ROM (Range of Motion)
I. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah melalui CSL ini diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan pemeriksaan ROM
J. ALAT DAN BAHAN
1. Bed periksa pasien
2. Meja dan kursi periksa
3. Goniometer
K. SKENARIO
Pasien pria gemuk, berusia 48 tahun datang dengan keluhan nyeri tajam pada sendi lutut sebelah
kanan. Keluhan sudah dirasakan hilang timbul selama 2 bulan belakangan, namun selama 3 hari ini
keluhan dirasa terus menerus dan memberat. Keluhan disertai dengan gerak sendi terbatas karena
nyeri, sulit untuk ditekuk maupun diluruskan, dan rasa kaku sementara pada sendi tersebut setelah
bangun tidur. Keluhan bertambah nyeri apabila sendi digerakkan, sedangkan bila beristirahat
keluhan berkurang. Untuk menegakkan diagnosis anda akan melakukan pemeriksaan fisik yang
sesuai.
L. DASAR TEORI
1. Pemeriksaan Anggota Gerak
Pada pemeriksaan anggota gerak dilakukan penilaian terhadap keadaan tulang, otot serta
sendi. Pemeriksaan dilakukan dengan inspeksi kemudian diikuti dengan palpasi serta perkusi
seperti yang telah dipelajari pada blok sebelumnya.
Kelainan pada anggota gerak dapat terjadi:
a. Berbagai kelainan kongenital dapat terjadi pada ekstremitas superior maupun inferior,
diantaranya amelia (tidak terdapatnya semua anggota gerak), ekstromelia (tidak adanya
salah satu anggota gerak), fokomelia (anggota gerak bagian proksimal yang pendek),
sindaktili (bergabungnya jari-jari), atau polidaktili (jumlah jari lebih dari normal).
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 147
Buku Panduan CSL 2 2017
b. Fraktur, dislokasi, hemangioma yang besar, limfangioma, fistula arteriovena,
neurofibromatosis dapat menyebabkan panjang dan bentuk ekstremitas kanan dan kiri tidak
sama.
c. Pada keadaan yang menyebabkan hipoksia kronik (penyakit jantung bawaan sianotik,
penyakit paru kronik) dan dapat pula disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit hati
kronik, endokarditis dan beberapa keganasan menyebabkan adanya jari-jari tabuh pada
tangan dan kaki. Tanda dini dari jari tabuh adalah menaiknya dasar kuku, pada stadium
selanjutnya seluruh bagian distal jari dan kuku mengembang dan membundar.
d. Nyeri tekan pada angggota gerak paling sering disebabkan oleh trauma dan infeksi. Nyeri
tekan pada m. Sartorius dapat merupakan tanda dari meningitis tuberculosa. Tiap rasanyeri
pada bagian distal tulang harus dicurigai kemungkinan terdapatnya osteomyelitis.
e. Gangren atau nekrosis jaringan akibat sumbatan pembuluh darah. Proses ini mula-mula
ditandai dengan anggota gerak yang dingin, pucat, kekuatan ototnya menghilang, serta rasa
nyeri. Dengan berlanjutnya proses nekrosis, maka daerah itu menjadi hipoestesi dan
bewarna hitam.
f. Disamping deformitas, tanda fraktur lainnya adalah nyeri, krepitasi serta gangguan fungsi
anggota gerak.
g. Kelainan bentuk tulang. Seringkali sampai lebih kurang satu tahun setelah anak dapat
berjalan, bentuk tibia melengkung keluar (genu varum). Genu valgum, tungkai berbentuk
huruf X seringkali didapatkan pada anak berumur 2-5 tahun yang masih dikategorikan
normal, akan tetapi dapat ditemukan pada anak dengan poliomyelitis, rakitis, sifilis, atau pada
anak yang posisi kedua kakinya pronasi.
h. Kelainan posisi kaki, misalnya club foot, pes kavus, pes ekuinus.
i. Gaya berjalan berupa kaki menyeret (foot drop), gaya berjalan seperti menggunting (scissors
gait), ataksia (cara berjalan yang canggung dan meluas).
Hal penting yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan sendi mayor:
a. Inspeksi sendi untuk melihat simetris atau tidak, alignment dan deformitas tulang
b. Inspeksi dan palpasi jaringan sekitar, lihat perubahan kulit, nodul, atrofi otot dan krepitasi
c. ROM dan manuver tiap sendi
d. Penilaian tanda inflamasi seperti bengkak, hangat, nyeri dan nyeri tekan dan kemerahan
Tanda-tanda radang sendi seperti RA, Demam Rematik, Serum Sickness gerakan menjadi
terbatas akibat rasa nyeri spasme otot dan tendon daerah sekitarnya. Adanya deformitas sendi
pergelangan tangan, siku, bahu, sendi sternoclavicularis, temporomandibularis dan sendi
panggul bisa menjadi tanda adanya subluksasi atau dislokasi.
2. Range Of Motion (ROM)
Pemeriksaan range of motion (ROM) adalah pemeriksaan dengan melakukan pengukuran luas
gerakan sendi (derajat) yang terjadi dari kontraksi dan pergerakan otot. Pemeriksaan dilakukan
dengan meminta klien menggerakan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik
secara aktif ataupun pasif.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 148
Buku Panduan CSL 2 2017
Tujuan pemeriksaan range of motion adalah:
a. Meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot.
b. Mencegah kontraktur dan kekakuan pada sendi
Jenis ROM :
a. ROM pasif, pemeriksa melakukan gerakan persendian klien sesuai dengan rentang gerak
yang normal (klien pasif). Kekuatan otot 50 %
b. ROM aktif, pemeriksa memberikan motivasi dan membimbing klien dalam melaksanakan
pergerakan sendi secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi normal (klien aktif).
Kekuatan otot 75 %
f. Supinasi
Jenis gerakan : g. Pronasi
a. Fleksi h. Abduksi
i. Aduksi
b. Ekstensi
j. Oposisi
c. Hiper ekstensi
d. Rotasi
e. Sirkumduksi
Sendi yang digerakan :
a. ROM Aktif
Seluruh tubuh dari kepala sampai ujung jari kaki oleh klien sendiri secara aktif.
b. ROM Pasif
Seluruh persendian tubuh atau hanya pada ekstremitas yang terganggu dan klien tidak
mampu melaksanakannya secara mandiri.
• Leher (fleksi/ekstensi, fleksi lateral)
• Bahu tangan kanan dan kiri (fkesi/ekstensi, abduksi/adduksi, Rotasi bahu)
• Siku tangan kanan dan kiri (fleksi/ekstensi, pronasi/supinasi)
• Pergelangan tangan (fleksi/ekstensi/hiperekstensi, abduksi/adduksi)
• Jari-jari tangan (fleksi/ekstensi/hiperekstensi, abduksi/ adduksi, oposisi)
• Pinggul dan lutut (fleksi/ekstensi, abduksi/adduksi, rotasi internal/eksternal)
• Pergelangan kaki (fleksi/ekstensi, rotasi)
• Jari kaki (fleksi/ekstensi)
Indikasi :
a. Stroke atau penurunan tingkat kesadaran
b. Kelemahan otot
c. Fase rehabilitasi fisik
d. Klien dengan tirah baring lama
Kontra Indikasi :
a. Trombus/emboli pada pembuluh darah
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 149
Buku Panduan CSL 2 2017
b. Kelainan sendi atau tulang
c. Klien fase imobilisasi karena kasus penyakit (misalnya: jantung)
Nilai Normal ROM:
Pemeriksaan Goniometri
Geniometri
Istilah goniometri berasal dari dua kata dalam bahasa yunani yaitu gonia yang berarti sudut dan
metron yang berarti ukur. Oleh karena itu goniometri berkaitan dengan pengukuran sudut,
khususnya sudut yang dihasilkan dari sendi melalui tulang-tulang ditubuh manusia. Goniometri
merupakan bagian yang penting dari keseluruhan evaluasi sendi juga meliputi jaringan lunak.
Goniometer digunakan untuk mengukur dan mendata kemampuan gerakan sendi aktif dan pasif.
Goniometer juga digunakan untuk menggambarkan secara akurat posisi abnormal sendi. Pada
CSL 2 ini pemeriksaan goniometri beluum dilakukan.
Prosedur
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 150
Buku Panduan CSL 2 2017
Menentukan aksis gerakan sendi yang akan diukur.
1. Meletakkan goniometer :
a. Aksis goniometer pada aksis gerak sendi.
b. Tangkai statik goniometer sejajar terhadap aksis longitudinal segmen tubuh yang statik.
c. Tangkai dinamik goniometer sejajar terhadap aksis longitudinal
2. Membaca besaran lingkup gerak sendi (LGS) pada posisi awal pengukuran dan
mendokumentasikannya
3. Menggerakkan sendi yang diukur secara pasif, sampai LGS maksimal yang ada
4. Mebaca besaran LGS
Gambar. Goniometer & Pemeriksaan ROM dengan menggunakan goniometer
M. PROSEDUR
1. PEMERIKSAAN SENDI BAHU
a. Inspeksi
• Inspeksi apakah terdapat deformitas, pembengkakan, atrofi otot atau fasikulasi.
• Jika ada riwayat nyeri bahu, minta pasien untuk menunjuk lokasi nyeri karena lokasi nyeri
bisa menjadi petunjuk letak lesi, misalnya :
Tepat diatas bahu, menyebar sampai ke leher : sendi acromioclavicular
Lateral bahu, menyebar ke insersi dari musculus deltoideus – lesi dari cuff rotator
Bahu bagian depan : lesi dari tendon bicipitalis
b. ROM
• Selama melakukan pemeriksaan ROM bahu, pemeriksa menempatkan tangannya pada
bahu pasien untuk mendeteksi ada tidaknya kresipitasi.
• Minta pasien untuk mengangkat lengannya (abduksi) setinggi bahu (90°) dengan telapak
tangan menghadap ke atas (untuk menilai pergerakan glenohumeralis)
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 151
Buku Panduan CSL 2 2017
• Kemudian angkat lengan pada posisi vertical di atas kepala dengan telapak tangan saling
berhadapan (untuk menilai pergerakan scapulothoracalis sebesar 60°dan kombinasi
pergerakan glenohumerale dan scapulothoracalis pada aduksi 30°)
Gambar Prosedur pemeriksaan ROM sendi bahu
2. PEMERIKSAAN SIKU
a. Inspeksi
• Topang lengan pasien dengan tangan pemeriksa sehingga siku menjadi fleksi 70°.
• Inspeksi medial dan lateral epicondylus dan olecranon.
• Inspeksi kontur dari siku, termasuk permukaan ekstensor dari ulna. Catat adanya nodul
atau pembengkakan.
b. Palpasi
• Palpasi daerah olekranon dan tekan epicondylus untuk nyeri tekan, catat jika ada dislokasi
dari olekranon.
• Palpasi grooves antara epicondylus dan olekranon, perhatikan adakah nyeri,
pembengkakan atau penebalan
c. Pemeriksaan ROM Siku
• Pemeriksaan rom siku mencakup gerakan fleksi dan ekstensi siku serta gerakan pronasi
dan supinasi lengan bawah.
• Pada saat pemeriksaan dengan pronasi dan supinasi, sebelumnya mintalah pasien untuk
memposisikan lengannya fleksi pada siku untuk meminimalisasi gerakan sendi bahu.
Gambar. Pemeriksaan ROM siku
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 152
Buku Panduan CSL 2 2017
3. PEMERIKSAAN PERGELANGAN TANGAN DAN JARI TANGAN
a. Inspeksi
• Inspeksi daerah palmar dan dorsal dari tangan, juga tulang dari setiap jari tangan apakah
terdapat deformitas, pembengkakan atau angulasi.
b. Palpasi
• Palpasi daerah pergelangan tangan pada bagian distal radius dan ulna dengan
menggunakan kedua ibu jari pada bagian dorsum pergelangan tangan.
• Perhatikan adakah pembengkakan, bogginess atau nyeri. Nyeri daerah distal radius dapat
menjadi pertanda adanya fraktur colless.
• Palpasi daerah jari tangan PIP dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk,
• Perhatikan apakah terdapat nyeri, pembengkakan, dan pembesaran tulang. Bila
ditemukan nodul (pembesaran tulang ) biasanya merupakan tanda dari Osteoarthritis.
Gambar. Palpasi pergelangan tangan dan jari tangan
c. Pemeriksaan ROM pergelangan tangan
Flexion
• Tempatkan lengan bawah pasien di atas meja periksa, pemeriksa memegang siku pasien.
• Posisikan pergelangan tangan pasien pada posisi ekstensi dan jari pemeriksa pada
telapak tangan pasien.
• Minta pasien untuk memfleksikan pergelangan tangannya melawan gravitasi
Extension
• Tempatkan lengan bawah pasien di atas meja periksa, pemeriksa memegang siku pasien.
• Posisikan pergelangan tangan pasien pada posisi fleksi dan tempatkan tangan pemeriksa
pada punggung tangan pasien.
• Minta pasien untuk mengekstensikan pergelangan tangannya melawan gravitasi.
Ulnar and radial deviation
• Posisikan telapak tangan pasien menghadap ke bawah.
• Salah satu tangan pemeriksa memegang pergelangan tangan pasien dan tangan lainnya
menopang telapak tangan pasien
• Minta pasien untuk menggerakan pergelangan tangannya ke arah lateral dan medial.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 153
Buku Panduan CSL 2 2017
Gambar. Pemeriksaan ROM pergelangan tangan
d. Pemeriksaan ROM jari tangan
Flexion dan extension
• Minta pasien untuk mengepalkan tangannya kemudian memekarkan jari-jarinya secara
bergantian. Normalnya pergerakan tersebut dapat dilakukan dengan lancar.
Abduction dan adduction
• Minta pasien untuk memekarkan jari-jarinya (abduksi) dan merapatkan jarinya (adduksi)
secara bergantian.
• Pada ibu jari, nilailah pergerakan fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi dan oposisi:
• Tes Fleksi dengan meminta pasien untuk menggerakkan ibu jari menyilang telapak tangan
dan menyentuh dasar jari kelingking.
• Tes ekstensi dengan meminta pasien kembali menggerakkan ibu jarinya
• Tes Abduksi dengan meminta pasien untuk memposisikan jarinya dalam keadaan netral,
telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian gerakkan ibu jari ke arah anterior menjauh
dari telapak tangan
• Tes adduksi dengan gerakan kembali ibu jari ke arah belakang.
• Tes oposisi dengan meminta pasien untuk menggerakkan ibu jari menyilang telapak
tangan,ibu jari menyentuh setiap ujung jari yang lain.
Gambar. Pemeriksaan ROM jari tangan
4. PEMERIKSAAN LUTUT DAN EKSTREMITAS BAWAH
a. Inspeksi
• Inspeksi cara dan irama berjalan pasien saat memasuki ruang pemeriksaan. Perhatikan
bentuk dan kontur lutut, apakah terdapat atrofi m. quadriceps apakah terdapat
pembengkakan.
b. Palpasi
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 154
Buku Panduan CSL 2 2017
• Mintalah pasien untuk duduk di tepi bed pemeriksaan dengan lutut dalam posisi fleksi.
Pada posisi ini landmark tulang dapat lebih mudah terlihat sementara otot, tendon dan
ligament lebih rileks, sehingga palpasi lebih mudah dilakukan.
• Palpasi dan identifikasi condylus femoralis media dan lateral, epicondylus femoralis media
dan lateral
• Palpasilah ligamen, batas meniscus dan bursa dari lutut, perhatikan jika terdapat
kekakuan.
c. Pemeriksaan ROM lutut
• Prinsip pemeriksaan rom lutut adalah fleksi, ekstensi, rotasi internal dan eksternal.
• Minta pasien untuk menggerakan fleksi dan ekstensi lututnya dalam keadaan duduk.
• Jika diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan meminta pasien berjongkok-berdiri
yang juga dapat menilai keseimbangan pasien.
• Minta pasien untuk memutar kakinya kearah medial dan lateral untuk menilai rotasi.
Terkadang juga diperlukan pemeriksaan stabilitas ligament dan integritas meniscus
terutama jika terdapat riwayat trauma atau teraba kekakuan. Pemeriksaan tersebut
mencakup Abduction Stress Test, Adduction Stress Test, Anterior Drawer Sign, Lachman
Test, Posterior Drawer Sign, dan McMurray Test yang dapat Anda pelajari sendiri pada
literatur pemeriksaan fisik.
5. PEMERIKSAAN PERGELANGAN KAKI DAN KAKI
a. Inspeksi
• Inspeksi daerah pergelangan kaki dan kaki, perhatikan apakah terdapat deformitas,
pembengkakan, nodule dan atau calus
b. Palpasi
• Palpasi dengan menggunakan kedua ibu jari pada bagian anterior dari pergelangan kaki
dan perhatikan adakah pembengkakan dan nyeri. Nyeri lokal dapat ditemukan pada kasus
arthritis, cedera ligament, atau infeksi daerah pergelangan kaki.
• Palpasi juga dilakukan di sendi-sendi Metatarsofalang dengan cara menekan kaki dengan
menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Nyeri yang didapatkan oleh karena penekanan
bisa menjadi pertanda stadium awal dari RA atau inflamasi akut yang disebakan oleh
GOUT.
Gambar. Pemeriksaan pergelangan kaki dan kaki
c. Pemeriksaan ROM pergelangan kaki dan kaki
• ROM dari pergelangan kaki adalah dorsofleksi dan plantarfleksi.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 155
Buku Panduan CSL 2 2017
• ROM kaki terdiri dari eversi dan inversi dengan cara memegang pergelangan kaki dan
tumit kaki pasien kemudian minta pasien menggerakan kakinya inversi dan eversi.
Gambar. Pemeriksaan ROM pergelangan kaki dan kaki
N. DAFTAR PUSTAKA
• Bate’s barbara. Guide to Physical Examination. Lippincot. 2007. Chapter 15
• Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Jakarta: 2006
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 156
Buku Panduan CSL 2 2017
CEKLIST KETERAMPILAN PEMERIKSAAN RANGE OF MOTION (ROM)
No Aspek Feedback
INTERPERSONAL
1. Sambung Rasa dan Informed consent
Pemeriksaan Muskuloskeletal dan ROM
Sendi Bahu
2. Lakukan inspeksi:
Apakah terdapat deformitas, pembengkakan, atrofi otot atau fasikulasi
3. Jika ada riwayat nyeri bahu, minta pasien untuk menunjuk lokasi nyeri,
lakukan palpasi pada area tersebut.
Lakukan pemeriksaan ROM sendi bahu dengan memegang sendi
bahu pasien dan meminta pasien untuk berdiri pada posisi anatomis,
kemudian:
4. Gerakkan lengan atas ke arah anterior untuk menilai Fleksi (normal
1800)
5. Gerakkan lengan atas ke arah posterior untuk menilai Ekstensi
(normal 600)
6. Gerakkan lengan atas ke arah anterior setinggi bahu, kemudian
gerakkan ke arah lateral-medial untuk menilai Fleksi Horisontal
(normal 1350)
7. Gerakkan lengan atas ke arah lateral untuk menilai Abduksi (normal
1800)
8. Gerakkan lengan atas ke arah medial (menyentuh anterior tubuh)
untuk menilai Adduksi ( normal 750)
Sendi Siku
9. Lakukan inspeksi dengan menopang lengan pasien dengan tangan
pemeriksa sehingga siku menjadi fleksi 70°. Perhatikan epicondylus
medial dan lateral serta olecranon. Perhatikan kontur siku, apakah
terdapat nodul atau pembengkakan.
10. Lakukan palpasi daerah olekranon dan tekan epicondylus untuk nyeri
tekan. Perhatikan apakah terdapat dislokasi olekranon, adakah nyeri,
pembengkakan atau penebalan antara epicondylus dan olekranon.
Lakukan pemeriksaan ROM Siku dengan meminta pasien untuk
berdiri pada posisi anatomis, kemudian:
11. Melakukan gerakan fleksi-ekstensi pada sendi sikunya (normal 1500)
12. Memposisikan sikunya fleksi kemudian melakukan rotasi telapak
tangan menghadap ke bawah untuk menilai pronasi (normal 800)
13. Memposisikan sikunya fleksi kemudian melakukan rotasi telapak
tangan menghadap ke atas untuk menilai supinasi (normal 800)
Sendi Pergelangan Tangan dan Jari
14. Lakukan inspeksi daerah palmar dan dorsal tangan serta jari tangan,
perhatikan apakah terdapat deformitas, pembengkakan atau angulasi.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 157
Buku Panduan CSL 2 2017
15. Lakukan palpasi daerah pergelangan tangan pada bagian distal
radius dan ulna dengan menggunakan kedua ibu jari. Perhatikan
adakah pembengkakan, bogginess atau nyeri. Palpasi daerah jari
tangan dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Perhatikan
adakah nyeri, pembengkakan atau pembesaran tulang.
Lakukan pemeriksaan ROM pergelangan tangan dengan pasien
berdiri pada posisi anatomis, kemudian mengangkat lengan atas dan
lengan bawah setinggi bahu sejajar lantai
16. Flexion:
a. Posisikan telapak tangan supinasi sejajar lantai
b. Gerakkan telapak tangan ke bawah untuk menilai fleksi sendi
pergelangan tangan (normal 800)
17. Extension:
c. Posisikan telapak tangan supinasi sejajar lantai
Gerakkan telapak tangan keatas untuk menilai ekstensii sendi
pergelangan tangan (normal 700)
18. Ulnar and radial deviation:
a) Memposisikan telapak tangan pasien menghadap ke bawah.
b) Memegang pergelangan tangan pasien dan menopang telapak
tangan pasien
c) Meminta pasien untuk menggerakan pergelangan tangannya ke
arah lateral dan media
Lakukan pemeriksaan ROM jari tangan :
19. Flexion dan extension:
Meminta pasien untuk mengepalkan tangannya kemudian
memekarkan jari-jarinya secara bergantian
20. Abduction dan adduction:
Meminta pasien untuk memekarkan jari-jarinya (abduksi) dan
merapatkan jarinya (adduksi) secara bergantian
Lakukan pemeriksaan ROM ibu jari:
21. Tes Fleksi:
Meminta pasien untuk menggerakkan ibu jari menyilang telapak
tangan dan menyentuh dasar jari kelingking
22. Tes ekstensi :
Meminta pasien menggerakkan ibu jarinya ke arah posterior
23. Tes Abduksi:
Meminta pasien untuk memposisikan jarinya dalam keadaan netral,
telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian gerakkan ibu jari ke
arah lateral menjauh dari jari telunjuk.
24. Tes adduksi:
Meminta pasien menggerakan kembali ibu jari ke arah medial
mendekat jari telunjuk.
Lutut dan ekstremitas bawah
26. Lakukan inspeksi cara dan irama berjalan pasien. Perhatikan pula
bentuk dan kontur lutut, apakah terdapat atrofi M. quadriceps, apakah
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 158
Buku Panduan CSL 2 2017
terdapat pembengkakan.
27. Lakukan palpasi dengan meminta pasien untuk duduk di tepi bed
pemeriksaan dengan lutut fleksi. Palpasi dan identifikasi condylus
femoralis media dan lateral, epicondylus femoralis media dan lateral
serta ligamen, batas meniscus, perhatikan jika terdapat kekakuan.
Lakukan pemeriksaan ROM lutut:
28. Fleksi dan Ekstensi:
Meminta pasien untuk menggerakan fleksi dan ekstensi lututnya
dalam keadaan duduk.
29. Rotasi internal dan eksternal:
Meminta pasien untuk memutar kakinya kearah medial dan lateral
Pergelangan kaki dan kaki
30. Lakukan inspeksi daerah pergelangan kaki dan kaki, perhatikan
apakah terdapat deformitas, pembengkakan, nodule dan atau calus
31. Lakukan palpasi dengan menggunakan kedua ibu jari pada bagian
anterior dari pergelangan kaki. Perhatikan adakah pembengkakan dan
nyeri. Palpasi sendi metatarsofalang dengan menekan kaki dengan
menggunakan ibu jari dan jari telunjuk.Perhatikan adakah
pembengkakan dan nyeri
Lakukan pemeriksaan ROM pergelangan kaki & kaki dengan:
32. Meminta pasien melakukan gerakan dorsofleksi dan plantarfleksi
33. Eversi dan inversi:
Peganglah pergelangan kaki dan tumit kaki pasien
Pinta pasien menggerakan kakinya inversi (memutar ke medial) dan
eversi (memutar ke lateral)
PROFESIONALISME
34. Melakukan dengan percaya diri
35. Melakukan dengan kesalahan minimal
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 159
Buku Panduan CSL 2 2017
KERANGKA ANAMNESIS
A. TEMA
Keterampilan Anamnesis
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa mampu melakukan anamnesis dengan benar
2. Tujuan Instruksional Khusus
1. Mahasiswa mampu melakukan anamnesis mengenai keluhan utama yang membawa pasien
datang ke dokter
2. Mahasiswa mampu melakukan anamnesis mengenai riwayat penyakit sekarang
3. Mahasiswa mampu melakukan anamnesis mengenai riwayat penyakit dahulu
4. Mahasiswa mampu melakukan anamnesis mengenai riwayat penyakit keluarga
5. Mahasiswa mampu melakukan anamnesis mengenai riwayat personal atau riwayat sosial
C. ALAT DAN BAHAN
Meja dan kursi periksa
D. SKENARIO
Seorang pria datang dengan keluhan demam. Anda sebagai seorang dokter yang ingin mengetahui
riwayat penyakit pasien melakukan wawancara yang terstruktur dengan tujuan untuk
mengeksplorasi keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Bagaimanakah cara menggali
informasi mengenai penyakit pasien sehingga dapat ditegakkan diagnosis yang tepat?
E. DASAR TEORI
1. PENDAHULUAN
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 160
Buku Panduan CSL 2 2017
Dewasa ini, tantangan sebagi tenaga kesehatan semakin mempengaruhi kinerja tenaga
kesehatan tersebut dalam menangani pasien. Khususnya seorang dokter, sangat diperlukan
adanya kesiapan untuk berani melakukan tatap muka dan aktif dalam membangun keakraban
dengan pasiennya. Pada umumnya kontak pertama antara seorang dokter pasien dimulai dari
anamnesis. Dari sini hubungan terbangun sehingga akan memudahkan kerjasama dalam
memulai tahap-tahap pemeriksaan berikutnya.
Dalam menegakkan suatu diagnosis anamnesis mempunyai peranan yang sangat penting
bahkan terkadang merupakan satu-satunya petunjuk untuk menegakkan diagosis. Anamnesis
adalah suatu tehnik pemeriksaan yang dilakukan lewat suatu percakapan antara seorang dokter
dengan pasiennya secara langsung atau dengan orang lain yang mengetahui tentang kondisi
pasien, untuk mendapatkan data pasien beserta permasalahan medisnya.
Tujuan pertama anamnesis adalah memperoleh data atau informasi tentang permasalahan yang
sedang dialami atau dirasakan oleh pasien. Apabila anamnesis dilakukan dengan cermat maka
informasi yang didapatkan akan sangat berharga bagi penegakan diagnosis, bahkan tidak jarang
hanya dari anamnesis saja seorang dokter sudah dapat menegakkan diagnosis.
Secara umum sekitar 60-70% kemungkinan diagnosis yang benar sudah dapat ditegakkan
hanya dengan anamnesis yang benar. Tujuan berikutnya dari anamnesis adalah untuk
membangun hubungan yang baik antara seorang dokter dengan pasiennya. Umumnya seorang
pasien yang baru pertama kalinya bertemu dengan dokternya akan merasa canggung, tidak
nyaman dan takut, sehingga cederung tertutup. Tugas seorang lah untuk mencairkan hubungan
tersebut. Pemeriksaan anamnesis adalah pintu pembuka atau jembatan untuk membangun
hubungan dokter dan pasiennya sehingga dapat mengembangkan keterbukaan dan kerjasama
dari pasien untuk tahap-tahap pemeriksaan selanjutnya.
2. ISI
Definisi Anamnesis
Anamnesis berasal dari bahasa Yunani anamneses, yang artinya mengingat kembali.
Anamnesis merupakan pengambilan data yang dilakukan oleh seorang dokter dengan cara
melakukan serangkaian wawancara dengan pasien atau keluarga pasien atau dalam keadaan
tertentu dengan penolong pasien. Berbeda dengan wawancara biasa, anamnesis dilakukan
dengan cara yang khas, berdasarkan pengetahuan tentang penyakit dan dasar-dasar
pengetahuan yang ada di balik terjadinya suatu penyakit serta bertolak dari masalah yang
dikeluhkan oleh pasien. Jenis pertanyaan yang akan diajukan kepada pasien dalam anamnesis
sangat beragam dan bergantung pada beberapa faktor.
Tujuan Anamnesis
1. Memperoleh data atau informasi tentang permasalahan yang sedang dialami atau dirasakan
oleh pasien.
2. Membangun hubungan yang baik antara seorang dokter dan pasiennya.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 161
Buku Panduan CSL 2 2017
Jenis-jenis Anamnesis
1. Auto anamnesis, merupakan anamnesis yang didapat langsung dari keluhan pasien. Pasien
sendirilah yang menjawab semua pertanyaan dokter dan menceritakan permasalahannya. Ini
adalah cara anamnesis terbaik karena pasien sendirilah yang paling tepat untuk
menceritakan apa yang sesungguhnya dia rasakan.
2. Allo anamnesis atau hetero anamnesis, merupakan anamnesis yang didapat dari orang tua
atau sumber lain yang dekat dan tahu betul tentang riwayat pasien, dilakukan ketika pasien
tidak dapat berkomunikasi langsung dengan dokter. Tidak jarang dalam praktek sehari-hari
anamnesis dilakukan bersama-sama auto dan allo anamnesis.
Persiapan Anamnesis
Hal yang harus dikuasai dalam anamnesis antara lain :
1. Keterampilan proses: meliputi bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien, menggali dan
mendapatkan riwayat pasien, menggali dan mendapatkan riwayat pasien, kemampuan verbal
dan non-verbal yang digunakan, bagaimana menciptakan suatu hubungan dengan pasien,
serta bagaimana cara berkomunikasi secara terstruktur dan terorganisasi.
2. Keterampikan isi: yaitu keterampilan mengenai isi pokok dari pertanyaan dan respon yang
diberikan kepada pasien.
3. Keterampilan perseptual: yakni apa yang dipikirkan dan rasakan mempengaruhi pembuatan
keputusan internal.
Selain itu dokter juga perlu terampil dalam mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka
ataupun tertutup dan terampil dalam mendengarkan baik secara aktif, empatik, dan reflektif.
Wawancara yang dilakukan selama anamnesis harus berdasarkan five basic task of doctor
patient interview, sebagai berikut :
1. Initiating the session
a. Menetapkan hubungan awal
b. Mengidentifikasi keluhan
2. Gathering information
a. Mengeksplorasi masalah
b. Memahami pandangan pasien
c. Membuat struktur pada konsultasi pasien
3. Building relationship
a. Mengembangkan hubungan
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 162
Buku Panduan CSL 2 2017
b. Menyertai pasien
4. Explanation and planning
a. Mengoreksi jumlah dan jenis
b. Membantu pemahaman dan mengakuratkan daya ingat
5. Clossing the session
Menutup wawancara
Adapun hal yang harus diperhatikan oleh seorang dokter sebelum memulai wawancara, antara
lain :
1. Tempat dan suasana. Tempat dan suasana dimana anamnesis ini dilakukan harus
diusahakan cukup nyaman bagi pasien. Anamnesis akan berjalan lancar kalau tempat dan
suasana mendukung. Suasana diciptakan agar pasien merasa santai, tidak tegang dan tidak
merasa diinterogasi.
2. Penampilan dokter. Penampilan seorang dokter juga perlu diperhatikan karena ini akan
meningkatkan kepercayaan pasiennya. Seorang dokter yang tampak rapi dan bersih akan
lebih baik dari pada yang tampak lusuh dan kotor. Demikian juga seorang dokter yang
tampak ramah, santai akan lebih mudah melakukan anamnesis daripada yang tampak galak,
ketus dan tegang.
3. Periksa kartu dan data pasien. Sebelum anamnesis dilakukan sebaiknya periksa terlebih
dahulu kartu atau data pasien dan cocokkan dengan keberadaan pasiennya. Tidak tertutup
kemungkinan kadang-kadang terjadi kesalahan data pasien atau mungkin juga kesalahan
kartu data, misalkan pasien A tetapi kartu datanya milik pasien B, atau mungkin saja ada 2
pasien dengan nama yang sama persis. Untuk pasien lama lihat juga data-data pemeriksaan,
diagnosis dan terapi sebelumnya. Informasi data kesehatan sebelumnya seringkali berguna
untuk anamnesis dan pemeriksaan saat ini.
4. Dorongan kepada pasien untuk menceritakan keluhannya. Pada saat anamnesis dilakukan
berikan perhatian dan dorongan agar pasien dapat dengan leluasa menceritakan apa saja
keluhannya. Biarkan pasien bercerita dengan bahasanya sendiri. Ikuti cerita pasien, jangan
terus menerus memotong, tetapi arahkan bila melantur. Pada saat pasien bercerita, apabila
diperlukan ajukan pertanyaan-pertanyaan singkat untuk minta klarifikasi atau informasi lebih
detail dari keluhannya. Jaga agar jangan sampai terbawa cerita pasien sehingga melantur
kemana mana
5. Gunakan bahasa atau istilah yang dapat dimengerti. Selama tanya jawab berlangsung
gunakan bahasa atau istilah umum yang dapat dimengerti pasien. Apabila ada istilah yang
tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau sulit dimengerti, berikan penjelasan atau
deskripsi dari istilah tersebut.
6. Buat catatan. Adalah kebiasaan yang baik untuk membuat catatan-catatan kecil saat seorang
dokter melakukan anamnesis, terutama bila pasien yang mempunyai riwayat penyakit yang
panjang.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 163
Buku Panduan CSL 2 2017
7. Perhatikan pasiennya. Selama anamnesis berlangsung perhatikan posisi, sikap, cara bicara
dan gerak-gerik pasien. Apakah pasien dalam keadaaan sadar sepenuhnya atau apatis,
apakah dalam posisi bebas atau posisi letak paksa, apakah tampak santai atau menahan
sakit, apakah tampak sesak, apakah dapat bercerita dengan kalimat-kalimat panjang atau
terputus-putus, apakah tampak segar atau lesu, pucat dan lain-lain.
8. Gunakan metode yang sistematis. Anamnesis yag baik haruslah dilakukan dengan sistematis
menurut kerangka anamnesis yang baku. Anamnesis yang sistematis bertujuan untuk melihat
keterlibatan setiap sistem dalam penyakit yang sekarang diderita dan kemungkinan adanya
masalah lain selain masalah yang dikeluhkan oleh pasien. Dengan cara ini diharapkan tidak
ada data anamnesis yang tertinggal.
Cara Melakukan Anamnesis
Dalam menganamnesis pasien, ada baiknya jika seorang mengetahui data-data umum
mengenai pasien terlebih dahulu, seperti :
1. Nama pasien: sebaiknya nama lengkap bukan nama panggilan atau alias.
2. Jenis kelamin: sebagai kelengkapan harus juga ditulis datanya
3. Umur: terutama penting pada pasien anak-anak karena kadang-kadang digunakan untuk
menentukan dosis obat. Juga dapat digunakan untuk memperkirakan kemungkinan penyakit
yang diderita, beberapa penyakit khas untuk umur tertentu.
4. Alamat: apabila pasien sering berpindah-pindah tempat maka tanyakan bukan hanya alamat
sekarang saja tetapi juga alamat pada waktu pasien merasa sakit untuk pertama kalinya.
Data ini kadang diperlukan untuk mengetahui terjadinya wabah, penyakit endemis atau untuk
data epidemiologi penyakit.
5. Pekerjaan: bila seorang dokter mencurigai terdapatnya hubungan antara penyakit pasien
dengan pekerjaannya, maka tanyakan bukan hanya pekerjaan sekarang tetapi juga
pekerjaan-pekerjaan sebelumnya.
6. Perkawinan: kadang berguna untuk mengetahui latar belakang psikologi pasien.
7. Agama: keterangan ini berguna untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh
(pantangan) seorang pasien menurut agamanya.
8. Suku bangsa: berhubungan dengan kebiasaan tertentu atau penyakit-penyakit yang
berhubungan dengan ras atau suku bangsa tertetu.
Setelah melakukan pemeriksaan data-data tersebut, maka langkah selanjutnya adalah:
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 164
Buku Panduan CSL 2 2017
1. Menanyakan keluhan utama pasien
Keluhan utama adalah yang menyebabkan penderita datang berobat. Keluhan utama
merupakan titik tolak penelusuran informasi mengenai penyakit yang diderita pasien
2. Menanyakan riwayat penyakit sekarang
Merupakan tujuh macam pertanyaan yang bersifat pribadi dari diri pasien tersebut,
diantaranya:
• Onset: dari sejak kapan sakit atau keluhan tersebut dirasakan.
• Lokasi: di mana rasa sakit atau keluhan tersebut dirasakan (di bagian tubuh yang mana)
• Kronologis: bagaimana cerita tentang sakit atau keluhan tersebut hingga bisa sampai
seperti ini.
• Kualitas: rasa sakit dari keluhan pasien seperti apa (sakit sekali, sakit bila disentuh, dan
lain-lain).
• Kuantitas: apakah penyakitnya sering kumat, atau seberapa sering penyakit tersebut
menyerang pasien.
• Gejala penyerta atau keluhan penyerta: keluhan-keluhan lain.
• Faktor modifikasi: faktor yang memperberat atau memperingan penyakit dari pasien.
Faktor modifikasi juga terkadang dibagi menjadi faktor risiko dan faktor prognostik. Faktor
risiko adalah faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu penyakit,
sedangkan faktor prognostik adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan suatu
penyakit atau hasil pengobatan penyakit. Faktor risiko dan faktor prognostik dapat berasal
dari pasien, keluarganya maupun lingkungan.
3. Menanyakan Riwayat Penyakit Dahulu (Past health history) : keluhan seputar apakah dulu
pernah mengalami sakit yang sama seperti saat ini, apakah ada penyakit lain sebelumnya,
apakah dulu pernah dioperasi, atau pun jenis obat apa saja yang pernah dikonsumsi pasien
sebelumnya.
4. Menanyakan Riwayat Penyakit Dalam Keluarga: apakah ada keluarga atau kerabat dekat
yang pernah mengalami gangguan yang sama atau penyakit keturunan yang lain.
5. Menanyakan Riwayat Personal atau riwayat sosial: pertanyaan mengenai tempat bekerja,
pola makan setiap hari, aktivitas olahraga, perokok atau tidak, dan pernah meminum
minuman dengan kadar akohol tinggi atau tidak, serta keadaan lingkungan rumah.
Reanamnesis
Reanamnesis berarti anamnesis ulang atau pengambilan data anamnesis tambahan setelah
dokter melakukan pemeriksaan fisik atau setelah dokter merawat pasien. Reanamnesis kadang
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 165
Buku Panduan CSL 2 2017
kala diperlukan untuk mengkonfirmasi data yang dianggap kurang konsisten atau kurang
lengkap.
Ringkasan Anamnesis
Ringkasan anamnesis dibuat berdasarkan analisis data anamnesis. Dokter mengelompokkan
data yang diperoleh yang mengarah pada sindrom atau kriteria diagnostik yang berhubungan
dengan diagnosis tertentu. Ringkasan anamnesis menggunakan bahasa dokter, tidak lagi
menggunakan bahasa pasien.
Kesimpulan Anamnesis
Pada akhir anamnesis seorang dokter harus dapat membuat kesimpulan dari anamnesis yang
dilakukan. Kesimpulan tersebut berupa perkiraan diagnosis yang dapat berupa diagnosis tunggal
atau diagnosis banding dari beberapa penyakit. Kesimpulan yang dibuat haruslah logis dan
sesuai dengan keluhan utama pasien. Bila menjumpai kasus yang sulit dengan banyak keluhan
yang tidak dapat dibuat kesimpulannya, maka cobalah dengan membuat daftar masalah atau
keluhan pasien. Daftar tersebut kemudian dapat digunakan untuk memandu pemeriksaan fisik
atau pemeriksaan penunjang yang akan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya dapat dibuat
suatu diagosis kerja yang lebih terarah.
Panduan untuk Keluarga
Kelengkapan dan kebenaran data yang diberikan keluarga sangat berarti bagi dokter untuk
menentukan diagnosis penyakit. Keluarga tidak perlu merasa segan atau malu dalam
memberikan informasi. Kesalahan data akan mempengaruhi diagnosis dan tindakan dokter.
Dalam langkah anamnesis, dokter akan bertindak seperti seorang detektif yang menyelidiki
suatu kasus, jadi keluarga tidak perlu merasa bosan apabila untuk kepentingan tertentu dokter
menanyakan hal yang sama secara berulang. Sebaliknya kadangkala keluarga terpancing untuk
memberikan informasi yang tidak diperlukan oleh dokter, mungkin karena pasien atau keluarga
dapat merasakan kehangatan komunikasi yang diciptakan oleh dokter.
Tantangan dalam Anamnesis
Adapun beberapa tantangan dalam menganamnesis pasien, yaitu sebagai berikut :
1. Pasien yang tertutup. Anamnesis akan sulit dilakukan bila pasien membisu dan tidak mau
menjawab pertanyaan-pertanyaan dokternya. Keadaan ini dapat disebabkan pasien merasa
cemas atau tertekan, tidak leluasa menceritakan keluhannya atau dapat pula perilakunya
yang demikian karena gangguan depresi atau psikiatrik. Tergantung masalah dan situasinya
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 166
Buku Panduan CSL 2 2017
kadang perlu orang lain (keluarga atau orang-orang terdekat) untuk mendampingi dan
menjawab pertanyaan dokter (heteroanamnesis), tetapi kadang pula lebih baik tidak ada
seorangpun kecuali pasien dan dokternya. Bila pasien dirawat di rumah sakit maka
anamnesis dapat dilanjutkan pada hari-hari berikutnya setelah pasien lebih tenang dan lebih
terbuka.
2. Pasien yang terlalu banyak keluhan. Sebaliknya tidak jarang seorang pasien datang ke dokter
dengan begitu banyak keluhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tugas seorang dokter
untuk memilah-milah keluhan mana yang merupakan keluhan utamanya dan mana yang
hanya keluh kesah. Diperlukan kepekaan dan latihan untuk membedakan mana yang
merupakan keluhan yang sesungguhnya dan mana yang merupakan keluhan mengada-ada.
Apabila benar-benar pasien mempuyai banyak keluhan harus dipertimbangkan apakah
semua keluhan itu merujuk pada satu penyakit atau kebetulan pada saat tersebut ada
beberapa penyakit yang sekaligus dideritanya.
3. Hambatan bahasa dan atau intelektual. Seorang dokter mungkin saja ditempatkan atau
bertugas disuatu daerah yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa daerah yang
belum kita kuasai. Keadaan semacam ini dapat menyulitkan dalam pelaksanaan anamnesis.
Seorang dokter harus segera belajar bahasa daerah tersebut agar dapat memperlancar
anamnesis, dan bila perlu dapat meminta bantuan atau petugas kesehatan lainnya untuk
mendampingi dan membantu menerjemahkan selama anamnesis. Kesulitan yang sama
dapat terjadi ketika menghadapi pasien yang karena intelektualnya yang rendah tidak dapat
memahami pertanyaan atau penjelasan dokternya. Seorang dokter dituntut untuk mampu
melakukan anamnesis atau memberikan penjelasan dengan bahasa yang sangat sederhana
agar dapat dimengerti pasiennya.
4. Pasien dengan gangguan atau penyakit jiwa. Diperlukan satu tehnik anamnesis khusus bila
seorang dokter berhadapan dengan penderita gangguan atau penyakit jiwa. Mungkin saja
anamnesis akan sangat kacau, setiap pertanyaan tidak dijawab sebagaimana seharusnya.
Justru di dalam jawaban-jawaban yang kacau tersebut terdapat petunjuk-petunjuk untuk
menegakkan diagnosis. Seorang dokter tidak boleh bingung dan kehilangan kendali dalam
melakukan anamnesis pada kasus-kasus ini.
5. Pasien yang cenderung marah dan menyalahkan. Tidak jarang dijumpai pasien-pasien yang
datang ke dokter sudah dalam keadaan marah dan cenderung menyalahkan. Selama
anamnesis mereka menyalahkan semua dokter yang pernah memeriksanya, menyalahkan
keluarga atau orang lain atas masalah atau keluhan yang dideritanya. Umumnya ini terjadi
pada pasien-pasien yang tidak mau menerima kenyataan diagnosis atau penyakit yang
dideritanya. Sebagai seorang dokter kita tidak boleh ikut terpancing dengan menyalahkan
sejawat dokter lain karena hal tersebut sangat tidak etis. Seorang dokter juga tidak boleh
terpancing dengan gaya dan pembawaan pasiennya sehingga terintimidasi dan menjadi takut
untuk melakukan anamnesis dan membuat diagnosis yang benar.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 167
Buku Panduan CSL 2 2017
3. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan :
1. Anamnesis adalah pengambilan data yang dilakukan oleh seorang dokter dengan cara
melakukan serangkaian wawancara dengan pasien atau keluarga pasien atau dalam
keadaan tertentu dengan penolong pasien. Berbeda dengan wawancara biasa, anamnesis
dilakukan dengan cara yang khas, berdasarkan pengetahuan tentang penyakit dan dasar-
dasar pengetahuan yang ada di balik terjadinya suatu penyakit serta bertolak dari masalah
yang dikeluhkan oleh pasien.
2. Berdasarkan anamnesis yang baik dokter akan menanyakan beberapa hal yaitu :
1. Identifikasi pasien
2. Keluhan utama
3. Riwayat Penyakit Sekarang :
• Onset
• Lokasi
• Kronologis
• Kualitas
• Kuantitas
• Gejala penyerta atau keluhan penyerta
• Faktor modifikasi
4. Riwayat Penyakit Dahulu (Past health history)
5. Riwayat Penyakit Dalam Keluarga
6. Riwayat Personal atau riwayat sosial
7. Ringkasan anamnesis dan kesimpulan anamnesis
F. PROSEDUR
1. Item Interaksi dokter-pasien
• Senyum, salam, sapa & membina sambung rasa;
• Menjelaskan prosedur dan melakukan informed consent sebelum melakukan pemeriksaan.
2. Menanyakan dan menuliskan data-data umum mengenai pasien
Menanyakan dan menuliskan: Nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat, pekerjaan,
perkawinan, agama, suku bangsa.
3. Menanyakan dan menuliskan keluhan utama
Menanyakan keluhan yang menyebabkan penderita datang berobat/ke dokter dan
menuliskannya di lembar rekam medis.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 168
Buku Panduan CSL 2 2017
4. Menanyakan dan menuliskan riwayat penyakit sekarang
Menanyakan bagaimana onset, lokasi, kronologis, kualitas, kuantitas, gejala penyerta, dan faktor
modifikasi dan menuliskannya di rekam medis.
5. Menanyakan dan menuliskan riwayat penyakit dahulu
Menanyakan keluhan seputar apakah dulu pernah mengalami sakit yang sama seperti saat ini,
apakah ada penyakit lain sebelumnya, apakah dulu pernah dioperasi, atau pun jenis obat apa
saja yang pernah dikonsumsi pasien sebelumnya serta adakah riwayat alergi terhadap obat
obatan tertentu.
6. Menanyakan dan menuliskan riwayat penyakit dalam keluarga
Menanyakan apakah ada keluarga, kerabat dekat yang pernah mengalami gangguan atau
keluhan yang sama serta penyakit keturunan yang lain.
7. Menanyakan dan menuliskan riwayat personal dan kehidupan sosial
Menanyakan pertanyaan mengenai tempat bekerja, pola makan setiap hari, aktivitas olahraga,
perokok atau tidak, dan pernah meminum minuman dengan kadar akohol tinggi atau tidak, serta
keadaan lingkungan rumah.
8. Membuat ringkasan anamnesis dan kesimpulan anamnesis
Mengelompokkan data yang diperoleh yang mengarah pada sindrom atau kriteria diagnostik
yang berhubungan dengan diagnosis tertentu, dan membuat kesimpulan dari anamnesis yang
berupa perkiraan diagnosis yang dapat berupa diagnosis tunggal dan diagnosis banding dari
beberapa penyakit. Mengakhiri pemeriksaan dengan baik dan menjelaskan hasil pemeriksaan
kepada pasien.
9. Item Professionalisme
• Percaya diri, minimal error
• Penalaran klinik baik dan bersesuaian dengan kasus
• Memperhatikan aspek kerahasiaan & etika pemeriksaan kepada pasien
G. DAFTAR PUSTAKA
1. Elsevier. Swartz: Textbook of Physical Diagnosis. History and Examination. 5e –
www.studentconsult.com didownload dari
http://www.studentconsult.com/content/default.cfm?ISBN=141600307X&ID=S1
2. Guyton and Hall, 1996 , Fisiologi Kedokteran, edisi 9,,EGC,
3. Snell,Richard S, 2006, Anatomi Klinik Untuk Mahasiswa Kedokteran, edisi 6, EGC, Jakarta.
4. Szilagy, Peter G. , 2002 , Bate's guide to physical examination, McGraw – Hill , Chapter 5: 155-
208
5. Harrison, 2005, Principles of Internal Medicine, edisi 16,McGraw – Hill, Part 14,2067 – 2231
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 169
Buku Panduan CSL 2 2017
CEKLIST KETRAMPILAN ANAMNESIS
Feedback
No Item Penilaian
INTERPERSONAL
1 Senyum, salam, sapa & membina sambung rasa
2 Menjelaskan prosedur dan melakukan Informed consent
sebelum melakukan pemeriksaan
CONTENT
3 Menanyakan data-data umum mengenai pasien
Menanyakan: Nama pasien, Jenis kelamin, Umur, Alamat,
Pekerjaan, Perkawinan, Agama, Suku bangsa
4 Menanyakan keluhan utama
Menanyakan keluhan hal menyebabkan penderita datang
berobat
5 Menanyakan riwayat penyakit sekarang
Menanyakan bagaimana onset, lokasi, kronologis, kualitas,
kuantitas, gejala penyerta, dan faktor modifikasi
6 Menanyakan riwayat penyakit dahulu
Menanyakan keluhan seputar apakah dulu pernah mengalami
sakit yang sama seperti saat ini, apakah ada penyakit lain
sebelumnya, apakah dulu pernah dioperasi, atau pun jenis obat
apa saja yang pernah dikonsumsi pasien sebelumnya.
7 Menanyakan riwayat penyakit dalam keluarga
Menanyakan apakah ada keluarga atau kerabat dekat yang
pernah mengalami gangguan yang sama atau penyakit
keturunan yang lain.
8 Menanyakan riwayat personal dan kehidupan sosial
Menanyakan pertanyaan mengenai tempat bekerja, pola makan
setiap hari, aktivitas olahraga, perokok atau tidak, dan pernah
meminum minuman dengan kadar akohol tinggi atau tidak.
9 Membuat ringkasan anamnesis dan kesimpulan anamnesis
Mengelompokkan data yang diperoleh yang mengarah pada
sindrom atau kriteria diagnostik yang berhubungan dengan
diagnosis tertentu, dan membuat kesimpulan dari anamnesis
yang berupa perkiraan diagnosis yang dapat berupa diagnosis
tunggal atau diagnosis banding dari beberapa penyakit.
10 Mengakhiri pemeriksaan dengan baik dan menjelaskan hasil
pemeriksaan kepada pasien
PROFESIONALISME
11 Percaya diri, minimal error
12 Penalaran klinik baik dan bersesuaian dengan kasus
13 Memperhatikan aspek kerahasiaan & etika pemeriksaan kepada
pasien
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 170
Buku Panduan CSL 2 2017
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 171
Buku Panduan CSL 2 2017
REKAM MEDIS, SURAT RUJUKAN,
DAN FORM PERMINTAAN
PEMERIKSAAN PENUNJANG
A. TEMA
Keterampilan komunikasi pembuatan dan pengisian rekam medis
B. TUJUAN
1. Mampu melakukan pengisian rekam medis, form rujukan, dan form permintaan pemeriksaan
penunjang dengan benar
2. Mampu menjelaskan manfaat pengisian rekam medis, surat rujukan, dan form permintaan
pemeriksaan penunjang
3. Mampu menjelaskan jenis jenis rekam medis
C. ALAT DAN BAHAN
1. Lembar rekam medis
2. Lembar rujukan
3. Lembar form pemeriksaan penunjang
4. Alat Tulis
5. Meja, kursi dan bed pemeriksaan
D. SKENARIO
Anda seorang dokter yang baru saja membuka praktek umum di daerah tempat tinggal anda. Pada
hari itu datang pasien yaitu seorang anak laki-laki usia 5 tahun yang diantar ibunya karena mencret
sejak 1 hari. Setelah dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pengobatan yang sesuai, anda
hendak membuat sebuah catatan rekam medis yang baik agar mudah dalam melakukan tindak
lanjut dikemudian hari.
E. DASAR TEORI
1. Pengertian
Rekam medis adalah suatu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas
pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada
pasien.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 172
Buku Panduan CSL 2 2017
Formulir permintaan penunjang memuat informasi permintaan pemeriksaan penunjang yang
mencangkup informasi pasien, jenis spesimen, asal spesimen, ataupun jenis pemeriksaan
penunjang lainnya (misal radiologi, dll.), tanggal pengambilan. Formulis permintaan penunjang
merupakan formulir yang dibutuhkan untuk pengajuan pemeriksaan penunjang terhadap pasien.
Surat rujukan adalah surat pengantar tenaga medis dalam hal ini ditujukan kepada dokter
maupun dokter gigi secara tertulis yang bertujuan sebagai advice (petunjuk pengobatan)
maupun pengobatan secara lebih lanjut kepada tenaga medis yang lebih berkompeten dalam
bidangnya. Setelah surat rujukan diberikan oleh dokter melalui pasien kepada dokter yang lebih
berkompeten, biasanya akan ada surat rujukan balasan yang berikan oleh dokter/dokter gigi
terujuk kepada dokter perujuk melalui pasien yang menyatakan bahwa telah dilakukan
pengobatan/perawatan, atau jawaban advice dari dokter/dokter gigi perujuk.
2. Manfaat rekam medis
Manfaat rekam medis adalah:
1. Sebagai dasar pemeliharaan dan pengobatan pasien
2. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hokum
3. Bahan untuk kepentingan penelitian
4. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
5. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistic kesehatan
Rekam medis dari rumah sakit harus memuat informasi yang cukup untuk menetapkan
diagnosis, terapi dan hasil terapi secara akurat. Rekam medis setiap rumah sakit sangat
bervariasi tetapi pada umumnya terdiri dari bagian informasi umum dan informasi klinis.
3. Isi rekam medis
Rekam medis pasien rawat jalan
1. Identitas pasien
2. Tanggal dan waktu
3. Anamnesis, sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat perjalanan penyakit
4. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis
5. Diagnosis
6. Rencana penatalaksanaan
7. Pengobatan dan atau tindakan
8. Pelayanan lain yang telah diberikan
9. Persetujuan tindakan medis bila diperlukan
Rekam medis pasien rawat inap
1. Identitas pasien
2. Tanggal dan waktu
3. Anamnesis, sekurang kurangnya keluhan dan riwayat perjalanan penyakit
4. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis
5. Diagnosis
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 173
Buku Panduan CSL 2 2017
6. Rencana penatalaksanaan
7. Pengobatan dan atau tindakan
8. Pelayanan lain yang telah diberikan
9. Persetujuan tindakan medis bila diperlukan
10. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan
11. Ringkasan pulang
12. Nama dan tanda tangan dokter atau tenaga kesehatan tertentu yang melakukan pelayanan
kesehatan
13. Pelayanan kesehatan lain yang dilakukan tenaga kesehatan tertentu
Rekam medis pasien gawat darurat
1. Identitas pasien
2. Kondisi saat tiba di sarana pelayanan kesehatan
3. Identitas pengantar pasien
4. Tanggal dan waktu
5. Anamnesis, sekurang kurangnya keluhan dan riwayat perjalanan penyakit
6. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis
7. Diagnosis
8. Pengobatan dan atau tindakan
9. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan UGD dan rencana tindak lanjut
10. Nama dan tanda tangan dokter atau tenaga kesehatan tertentu yang melakukan pelayanan
kesehatan
11. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang dipindahkan ke sarana kesehatan
lain
12. Pelayanan lain yang telah diberikan
Rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan
dan setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang
memberikan pelayanan atau tindakan.
4. Surat Rujukan
Surat rujukan umumnya terdiri dari surat rujukan dan surat balasan rujukan.
5. Surat rujukan berisi:
1. Tanggal rujukan dibuat
2. Nomor surat
3. Nama/Spesialisasi Dokter rujukan
4. Lokasi/alamat dokter rujukan
5. Kalimat permintaan/permohonan rujukan
6. Nama, umur, jenis kelamin, serta alamat pasien yang dirujuk
7. Hasil anamnesis pasien
8. Hasil pemeriksaan fisik pasien
9. Hasil pemeriksaan penunjang (bila ada)
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 174
Buku Panduan CSL 2 2017
10. Diagnosis sementara
11. Terapi/obat yang telah diberikan
12. Nama dokter pengirim/perujuk
13. Tanda tangan dokter pengirim/perujuk
Surat balasan rujukan berisi:
1. Tanggal balasan rujukan dibuat
2. Nama, umur, jenis kelamin, serta alamat pasien
3. Keterangan: keterangan umumnya berisi jawaban dokter konsulen. Dapat berupa konsul
selesai; Perlu kontrol kembali; Perlu konsul ke ahli lain; perlu tindakan medis lain; maupun
perlu dirawat dengan indikasi.
4. Hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan oleh dokter konsulen
5. Diagnosis
6. Terapi yang telah diberikan oleh dokter konsulen
7. Anjuran
8. Tanda tangan dokter konsulen
6. Form Permintaan Pemeriksaan Penunjang
Formulir permintaan pemeriksaan penunjang biasanya sudah tersedia daftar pemeriksaan yang
dapat dilakukan di fasilitas kesehatan terkait. Bila permintaan tidak terdapat dalam daftar
pemeriksaan, maka permintaan pemeriksaan dapat diisi pada kolom pemeriksaan lain-lain.
Form permintaan pemeriksaan penunjang umumnya dibagi menjadi permintaan pemeriksaan
laboratorium dan pemeriksaan pencitraan/radiologi. Pemeriksaan penunjang laboratorium
maupun radiologis terkadang membutuhkan perlakukan khusus terhadap pasien sebelum pasien
dapat diambil spesimennya atau sebelum pasien dapat dilakukan pemeriksaan radiologis. Untuk
itu seorang dokter harus paham kondisi klinis dan syarat pengambilan spesimen/pemeriksaan
radiologis.
Pada permintaan radiologis, keterangan klinis pasien yang akan dilakukan pemeriksaan
radiologis dan pembacaan hasil sangat dibutuhkan oleh radiolog. Sehingga dalam permintaan
pemeriksaan penunjang radiologis disertakan pula kondisi klinis pasien.
F. PROSEDUR
a) Tanyakan identitas pasien
b) Lakukan anamnesis
c) Lakukan pemeriksaan fisik
d) Isikan pada rekam medis
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 175
Buku Panduan CSL 2 2017
1. Identitas pasien
2. Tanggal dan waktu
3. Anamnesis, sekurang kurangnya keluhan dan riwayat perjalanan penyakit
4. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis
5. Diagnosis
6. Rencana penatalaksanaan
7. Pengobatan dan atau tindakan
8. Pelayanan lain yang telah diberikan
e) Mengisi formulir permintaan pemeriksaan penunjang
f) Mengisi surat rujukan
g) Beritahukan rencana penatalaksanaan.
G. DAFTAR PUSTAKA
• Anonim. Manual Rekam Medis : Konsil Kedokteran Indonesia. Jakarta. Indonesia
• Permenkes No.269/Menkes/per/III/2008
• UU RI No : 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Jakarta. Indonesia
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 176
Buku Panduan CSL 2 2017
Rekam Medis Pasien Poliklinik/Rawat Inap
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 177
Buku Panduan CSL 2 2017
Rekam Medis Pasien IGD
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 178
Buku Panduan CSL 2 2017
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 179
Buku Panduan CSL 2 2017
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 180
Buku Panduan CSL 2 2017
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 181
Buku Panduan CSL 2 2017
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 182
Buku Panduan CSL 2 2017
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 183
Buku Panduan CSL 2 2017
CEKLIST PEMBUATAN REKAM MEDIS, SURAT RUJUKAN, DAN FORM PERMINTAAN
PEMERIKSAAN PENUNJANG
No Item Latihan Feedback
Komunikasi dokter-pasien
1. Senyum Salam Sapa
2. Binalah sambung rasa yang baik dengan pasien
Item Prosedural
3. Lakukan anamnesis dengan baik (salam, sambung rasa, perkenalan,
identitas, keluhan utama, menggali keluhan utama & penyerta, RPS,
RPD, RPK, RPL)
4. Isi lembar rekam medis berupa :
✓ Identitas Pasien
5. ✓ Tanggal dan Waktu Pemeriksaan
6. ✓ Hasil Anamnesis
• Keluhan Utama & Menggali KU
• Keluhan Penyerta
• RPS, RPD, RPK/Lingkungan
7. Lakukan Pemeriksaan Fisik, Penunjang dan tindakan awal yang
diperlukan dengan tetap membina sambung rasa dengan pasien serta
informed consent jika diperlukan
8. Tuliskan hasil Pemeriksaan Fisik dan penunjang dengan benar pada
rekam medis (Status Generalis dan Lokalis)
9 . Tuliskan Diagnosis dan Diagnosis banding yang sesuai
10 Tuliskan terapi & tindakan yang telah diberikan serta rencana
tatalaksana lanjutan pada lembar Rekam Medis
11 Lakukan Planning Edukasi dengan baik
12 Tutup pemeriksaan dengan baik
13 Lengkapi rekam medis serta membubuhkan tanda tangan pada status
setelah selesai
14 Mengisi formulir pemeriksaan penunjang
15 Mengisi surat rujukan
Item Professionalisme
16 Percaya Diri
17 Minimal error
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 184
Buku Panduan CSL 2 2017
PEMERIKSAAN REFLEKS FISIOLOGIS
DAN PATOLOGIS
A. TEMA
Pemeriksaan refleks fisiologis dan reflek patologis
B. TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mampu melakukan pemeriksaan reflek fisiologis dan patologis
2. Mampu menjelaskan tujuan dan interpretasi hasil pemeriksaan reflek fisiologis dan patologis
3. Mampu melakukan penalaran klinik terhadap hasil pemeriksaan
C. ALAT DAN BAHAN
1. Reflek hammer
2. Meja pemeriksaan
D. SKENARIO
Tn.X, 48 tahun, diantar oleh keluarganya ke RS karena pagi ini tiba-tiba beliau jatuh pingsan setelah
bertengkar hebat dengan tetangganya, dan ketika sadar Tn.X menjadi sulit untuk menggerakkan
tangan dan kaki kanannya. Anda kebetulan yang saat itu sedang bertugas di UGD memeriksa Tn.X
dengan seksama, dan memang benar tangan dan kaki kanan beliau menjadi lemah.
E. DASAR TEORI
1. Refleks Fisiologis dan Patologis
Reflek adalah jawaban atas rangsang. Reflek neurologik tergantung pada suatu lengkung reflek
yang terdiri dari jalur aferen yang dicetus oleh reseptor dan sistem eferen yang mengaktivasi
organ efektor, serta hubungan antara kedua komponen. Misalnya reflek tendon yang timbul
karena adanya rangsang, yang akan diteruskan ke reseptor--serabut aferen--ganglion spinal--
serabut eferen—efektor (otot). Gerak otot reflektoris dapat ditimbulkan pada setiap orang sehat
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 185
Buku Panduan CSL 2 2017
(reflek fisiologis). Reflek regang otot adalah reflek yang timbul oleh regangan otot yang
disebabkan rangsangan dan sebagai jawabannya maka otot berkontraksi. Nama lain dari reflek
ini adalah reflek tendon atau reflek fisiologis. Pada kerusakan UMN dapat terjadi refleks yang
tidak dapat dibangkitkan pada orang –orang sehat, yang dinamakan refleks patologis.
Reflek patologis yang dikemukakan oleh Babinski (1896) menyatakan bahwa reflek superfisial
yang dibangkitkan pada keempat ekstremitas menjadi berubah jawabannya jika terdapat lesi
pada traktus piramidalis. Reflek, baik berupa lesi Upper Motor Neuron (UMN) atau Lower Motor
Neuron (LMN) yang pada ekstrimitas bawah tidak lagi terjadi plantar fleksi seperti pada orang
normal tetapi dorso fleksi ibu jari kaki disertai gerakan mekar jari-jari lainnya sedangkan pada
ekstrimitas atas (pada reflek hoffman trommer) akan timbul fleksi keempat jari, yang pada orang
normal tidak terjadi apa-apa.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan refleks fisiologis adalah:
• Penderita harus dalam keadaan santai. Bagian yang diperiksa harus dalam posisi sedemikian
rupa sehingga gerakan otot yang terjadi dapat muncul secara optimal
• Rangsangan harus diberikan secara cepat dan langsung. Pukulan tidak perlu terlalu keras
Gambar. Cara melakukan pukulan dengan menggunakan palu refleks
Penilaian hasil refleks
Refleks fisiologis dapat dinilai sebagai negatif, menurun, normal, meninggi dan hiperaktif
Ada pula yang menggunakan kriteria sebagai berikut :
0 : negatif
+1 : lemah (dari normal)
+2 : normal
+3 : meninggi
+4 : hiperaktif
Jenis refleks fisiologis
• Reflek bisep: dengan memberi rangsangan berupa ketoka pada tendon otot biseps maka
akan menimbulkan gerakan fleksi lengan bawah. Pusat reflek ini terletak di C5-C6
• Reflek tricep: dengan memberikan rangsangan berupa ketokan pada tendon otot triceps dan
sebagai jawabannya akan terjadi ektensi lengan bawah. Pusat refleks ini terletak di C6-C8
• Reflek patella: dengan memberi rangsangan pada tendon m quadriceps femoris dan sebagai
jawabannya akan terjadi gerakan ekstensi tungkai bawah. Pusat refleks terletak L2, L3, L4.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 186
Buku Panduan CSL 2 2017
• Reflek achilles: dengan memberi rangsangan pada tendon achilles dan sebagai jawabannya
akan terjadi gerakan plantar fleksi pada kaki. Pusat refleks melalui S1 dan S2
Jenis refleks patologis
• Hoffmann tromer
Jepit jari tengah pasien diantara telunjuk dan jari tengah pemeriksa. Gores dengan kuat jari
tengan dengan menggunakan ibu jari. Abnormal terjadi fleksi jari telunjuk serta fleksi dan
aduksi ibu jari.
• Reflek babinski
Lakukan goresan pada telapak kaki dari arah tumit ke arah jari melalui sisi lateral. Orang
normal akan memberikan respon fleksi jari-jari dan penarikan tungkai. Pada lesi UMN maka
akan timbul respon jempol kaki akan dorsofleksi, sedangkan jari-jari lain akan menyebar atau
membuka. Normal pada bayi masih ada.
• Reflek oppenheim
Lakukan goresan pada sepanjang tepi depan tulang tibia dari atas ke bawah, dengan kedua
jari telunjuk dan tengah. Jika positif maka akan timbul reflek seperti babinski
• Reflek gordon
Lakukan goresan/memencet otot gastrocnemius, jika positif maka akan timbul reflek seperti
babinski
• Reflek gonda
Lakukan penekanan/fleksikan jari ke-4 pedis kemudian lepaskan dengan cepat. Jika positif,
maka akan timbul reflek seperti babinski.
• Reflek schaefer
Lakukan pemencetan pada tendo achiles. Jika positif maka akan timbul reflek seperti babinski
• Reflek caddock
Lakukan goresan sepanjang tepi lateral punggung kaki dari maleolus lateral ke arah kaudal.
Jika positif maka akan timbul reflek seperti babinski.
F. PROSEDUR
Pemeriksaan Refleks Fisiologis
1. Pemeriksaan refleks biseps
a. Meminta pasien duduk dengan santai
b. Lengan dalam keadaan lemas, posisikan lengan bawah antara fleksi dan ekstensi serta
sedikit pronasi
c. Letakkan siku pasien pada lengan/tangan pemeriksa
d. Letakkan ibu jari di atas tendo biseps kemudian pukullah ibu jari tadi dengan refleks hammer
e. Reaksi utama adalah kontraksi otot biseps & fleksi lengan bawah
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 187
Buku Panduan CSL 2 2017
Gambar. Refleks Biseps
2. Pemeriksaan refleks triseps
a. Posisikan pasien sama dengan posisi pada pemeriksaan refleks biseps
b. instrusikan kepada pasien untuk melemaskan lengan dan relaksasi sempurna
c. Pukullah tendo yang lewat di fossa olekranon
d. Triseps akan kontraksi dengan sedikit menyentak (ekstensi lengan bawah di siku)
Gambar. Refleks Triseps
3. Pemeriksaan refleks patella
a. Posisikan pasien dalam posisi duduk dengan tungkai menjuntai
b. Raba daerah kanan-kiri tendo patella terlebih dulu untuk menentukan daerah yang tepat
c. Pegang paha pasien bagian distal dengan tangan pemeriksa sedangkan tangan yang lain
memukul tendo patella dengan palu refleks hammer secara cepat
d. Respon: ekstensi tungkai bawah
Gambar. Refleks Patella
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 188
Buku Panduan CSL 2 2017
4. Pemeriksaan refleks achilles
a. Meminta pasien duduk dengan tungkai menjuntai atau berbaring dimana sebagian tungkai
bawah & kakinya terjulur di luar meja pemeriksa
b. Regangkan tendo achilles dengan cara menahan ujung kaki ke arah dorsofleksi
c. Pukullah Tendo achilles dengan ringan tetapi cepat
d. Akan muncul gerakan fleksi kaki yang menyentak
Gambar. Refleks Achiles
Pemeriksaan Reflek Patologis
1. Plantar Response
a. Reflek Babinsky
Gores telapak kaki bagian lateral dari tumit menuju pangkal jari.
Gambar. Arah goresan dan reflek yang muncul pada reflek Babinski
b. Reflek Chaddock
Gores bagian lateral maleolus ke arah kaudal.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 189
Buku Panduan CSL 2 2017
Gambar. Arah goresan pada pemeriksaan reflek Chaddock
c. Reflek Gordon
Remas otot betis.
Gambar. Cara pemeriksaan reflek Gordon dan responnya
d. Reflek Gonda
Tekuk maksimal jari keempat kaki kemudian lepaskan tiba-tiba.
Gambar. Cara pemeriksaan reflek Gonda
e. Reflek Schaefer
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 190
Buku Panduan CSL 2 2017
Pencet tendon achilles dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk.
Gambar. Cara pemeriksaan reflek Schaefer
f. Reflek Oppenheim
Urut kuat tibia dan m. tibialis anterior dari proksimal ke distal.
Gambar. Cara pemeriksaan reflek Oppenheim
Kesimpulan keseluruhan untuk Refleks Plantar Response :
Normal : akan terlihat gerakan plantar fleksi kaki
Abnormal : akan terlihat gerakan dorsofleksi ibu jari disertai mekarnya jari-jari yang lain
2. Reflek Hoffman Tromner
• Pegang tangan pada pergelangan, jari-jari difleksikan.
• Jepit jari tengah pasien diantara telunjuk dan jari tengah pemeriksa.
• Gores dengan kuat jari tengan dengan menggunakan ibu jari.
• Abnormal terjadi fleksi jari telunjuk serta fleksi dan aduksi ibu jari.
Gambar. Cara pemeriksaan reflek Hoffman Tromner
G. DAFTAR PUSTAKA
1. Bahan kuliah Neurologi FK UNSRI, 2000
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 191
Buku Panduan CSL 2 2017
2. Bahan kuliah Neurologi FK UI, 2010
3. Panduan CSL Pemeriksaan Neuropsikiatri Unhas, 2010
4. Swartz, M.H., 1995. Buku Ajar Diagnostik Fisik. Jakarta: EGC
5. Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Jakarta: 2006
6. Lynn S. Bickley: Bate's guide to physical examination.
7. SM Lumbantobing: Neurologi Klinik, Pemeriksaan fisik dan mental. BP FKUI. Jakarta:2000
8. T Juwono: Pemeriksaan Klinik Neurologik Dalam Praktek. EGC. Jakarta: 2000
9. Burnside-Mc Glynn: Adams Diagnosis Fisik. Edisi 17. EGC. Jakarta: 1995
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 192
Buku Panduan CSL 2 2017
CEKLIST KETERAMPILAN PEMERIKSAAN REFLEKS FISIOLOGIS DAN PATOLOGIS
No Prosedur Feedback
INTERAKSI DOKTER – PASIEN
1.
Senyum, salam, sapa
2. Beritahukan kepada pasien mengenai tindakan yang akan
dilakukan dan persetujuan tindakan (informed consent)
PEMERIKSAAN REFLEKS FISIOLOGIS
3. Lakukan pemeriksaan reflek biseps
• Meminta pasien duduk dengan santai
• Posisikan lengan bawah pasien antara fleksi dan ekstensi serta
sedikit pronasi
• Letakkan siku pasien pada lengan/tangan pemeriksa
• Letakkan ibu jari di atas tendo biseps kemudian pukullah ibu jari
tadi dengan refleks hammer
• Hasil : Fleksi lengan bawah
4. Lakukan pemeriksaan reflek triseps
• Posisikan pasien sama dengan posisi pada pemeriksaan refleks
biseps
• Instruksikan kepada pasien untuk melemaskan lengan dan
relaksasi sempurna
• Pukullah tendo yang lewat di fossa olekranon
• Hasil : Ekstensi lengan bawah
5. Lakukan pemeriksaan reflek patella
• Posisikan pasien dalam posisi duduk dengan tungkai menjuntai
• Raba daerah kanan-kiri tendo patella terlebih dulu untuk
menentukan daerah yang tepat
• Pegang paha pasien bagian distal dengan tangan kiri sedangkan
tangan yang lain memukul tendo patella dengan palu refleks
hammer secara cepat
• Hasil : ekstensi tungkai bawah
6. Lakukan pemeriksaan reflek achilles
• Meminta pasien duduk dengan tungkai menjuntai atau berbaring
dimana sebagian tungkai bawah & kakinya terjulur di luar meja
pemeriksa
• Regangkan tendo achilles dengan cara menahan ujung kaki ke
arah dorsofleksi
• Pukullah Tendo achilles dengan ringan tetapi cepat
• Hasil : plantarfleksi
PEMERIKSAAN REFLEK PATOLOGIS
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 193
Buku Panduan CSL 2 2017
7. Lakukan pemeriksaan reflek babinski
Gores plantar pedis sisi lateral dari tumit ke kaudal
8. Lakukan pemeriksaan reflek Chaddock
Gores dorsum pedis pada maleolus lateral ke arah kaudal
9. Lakukan pemeriksaan reflek Gordon
Tekan/cubit otot gastrocnemius pasien
10 Lakukan pemeriksaan reflek Gonda
Fleksikan jari ke-4 pedis kemudian lepaskan secara cepat
11 Lakukan pemeriksaan reflek Oppenheim
Gosok sepanjang tulang tibia dengan menggunakan jari telunjuk
dan jari tengah
12 Lakukan pemeriksaan reflek Schaefer
Tekan/cubit tendon achiles dengan ibu jari dan telunjuk
13 Lakukan pemeriksaan reflek Hoffman Tromner
• Pegang tangan pada pergelangan, jari-jari difleksikan.
• Jepit jari tengah pasien diantara telunjuk dan jari tengah
pemeriksa.
• Gores dengan kuat jari tengan dengan menggunakan ibu jari.
PROFESIONALISME
18 Melakukan dengan penuh percaya diri
19
Melakukan dengan kesalahan minimal
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 194
Buku Panduan CSL 2 2017
PRINSIP STERILITAS
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 195
Buku Panduan CSL 2
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
196
Anda mungkin juga menyukai
- Bahasa Inggris Sistem 52M Volume 1Dari EverandBahasa Inggris Sistem 52M Volume 1Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (40)
- Pengambilan keputusan dalam 4 langkah: Strategi dan langkah operasional untuk pengambilan keputusan dan pilihan yang efektif dalam konteks yang tidak pastiDari EverandPengambilan keputusan dalam 4 langkah: Strategi dan langkah operasional untuk pengambilan keputusan dan pilihan yang efektif dalam konteks yang tidak pastiPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5)
- ILMU PERUBAHAN DALAM 4 LANGKAH: Strategi dan teknik operasional untuk memahami bagaimana menghasilkan perubahan signifikan dalam hidup Anda dan mempertahankannya dari waktu ke waktuDari EverandILMU PERUBAHAN DALAM 4 LANGKAH: Strategi dan teknik operasional untuk memahami bagaimana menghasilkan perubahan signifikan dalam hidup Anda dan mempertahankannya dari waktu ke waktuPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (6)
- Kepribadian: Pengantar ilmu kepribadian: apa itu kepribadian dan bagaimana menemukan melalui psikologi ilmiah bagaimana kepribadian mempengaruhi kehidupan kitaDari EverandKepribadian: Pengantar ilmu kepribadian: apa itu kepribadian dan bagaimana menemukan melalui psikologi ilmiah bagaimana kepribadian mempengaruhi kehidupan kitaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1)
- Analisis swot dalam 4 langkah: Bagaimana menggunakan matriks SWOT untuk membuat perbedaan dalam karir dan bisnisDari EverandAnalisis swot dalam 4 langkah: Bagaimana menggunakan matriks SWOT untuk membuat perbedaan dalam karir dan bisnisPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3)
- Bahasa Inggris Sistem 52M Volume 2Dari EverandBahasa Inggris Sistem 52M Volume 2Penilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (7)
- Kesehatan mental dan gangguan psikologis: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandKesehatan mental dan gangguan psikologis: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- Program Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaDari EverandProgram Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9)
- Buku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!Dari EverandBuku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (4)
- Pembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisDari EverandPembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (13)
- Panduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanDari EverandPanduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)
- Guideline Stroke 2011Dokumen132 halamanGuideline Stroke 2011Paijo Suseno88% (17)
- Buku Panduan CSL 2 TA 2016-2017Dokumen187 halamanBuku Panduan CSL 2 TA 2016-2017Ian Ivantirta100% (1)
- Logbook Anestesi New FIXDokumen43 halamanLogbook Anestesi New FIXpipitBelum ada peringkat
- Berdagang dengan bollinger bands menjadi mudah: Cara mempelajari cara menggunakan Bollinger Bands untuk berdagang online dengan suksesDari EverandBerdagang dengan bollinger bands menjadi mudah: Cara mempelajari cara menggunakan Bollinger Bands untuk berdagang online dengan suksesBelum ada peringkat
- BUKU PANDUAN TEKNIK PF Dan PROSEDUR PDFDokumen178 halamanBUKU PANDUAN TEKNIK PF Dan PROSEDUR PDFAnggun Permata Sari SuknaBelum ada peringkat
- Jurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Dari EverandJurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Penilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (7)
- Panduan PF & Prosedur IPD FKUIDokumen178 halamanPanduan PF & Prosedur IPD FKUIAraa Asuka100% (1)
- SOP Pemasangan Infus FK UNS PDFDokumen34 halamanSOP Pemasangan Infus FK UNS PDFNunung Firda IstiqomahBelum ada peringkat
- Pemeriksaan GinekologiDokumen19 halamanPemeriksaan GinekologiJuwita Desri AyuBelum ada peringkat
- Buku Panduan CSL 7Dokumen112 halamanBuku Panduan CSL 7Karen Kuniya100% (1)
- Buku Panduan CSL 1 2021Dokumen214 halamanBuku Panduan CSL 1 2021sarahBelum ada peringkat
- Buku Panduan CSL 1 2015Dokumen134 halamanBuku Panduan CSL 1 2015Nadila Ayuni PutriBelum ada peringkat
- Buku Panduan CSL 1 2015Dokumen134 halamanBuku Panduan CSL 1 2015Zhafran TobingBelum ada peringkat
- CSL DDTDokumen38 halamanCSL DDTDhiya AndiniBelum ada peringkat
- Modul CSL 4 2021Dokumen138 halamanModul CSL 4 2021Nur FadillaBelum ada peringkat
- Modul CSL 1Dokumen65 halamanModul CSL 1Aflin BiharBelum ada peringkat
- Manual SL PEM FISIK JANTUNG PARU - SMT II - 2018Dokumen43 halamanManual SL PEM FISIK JANTUNG PARU - SMT II - 2018JacobMsangBelum ada peringkat
- Cover Buku Panduan CSL 4 2016 Secured - UnlockedDokumen11 halamanCover Buku Panduan CSL 4 2016 Secured - UnlockedDhita Dwi NandaBelum ada peringkat
- 1.3 Buku Panduan Praktik Klinik 1 - Roro - 20192020 (Revisi 1 Bu Nova) PDFDokumen49 halaman1.3 Buku Panduan Praktik Klinik 1 - Roro - 20192020 (Revisi 1 Bu Nova) PDFdwi atikaBelum ada peringkat
- Pemeriksaan Fisik Head-to-Toe-1-8Dokumen8 halamanPemeriksaan Fisik Head-to-Toe-1-8Lisa Citra WildaniBelum ada peringkat
- Pemeriksaan Fisik Head To Toe 87182744Dokumen37 halamanPemeriksaan Fisik Head To Toe 87182744Riry MarthaBelum ada peringkat
- Logbook THT (1) RevisiDokumen50 halamanLogbook THT (1) Revisizuhdi azzyumar dhiniBelum ada peringkat
- Penuntun CSL Respirasi 2017-1Dokumen58 halamanPenuntun CSL Respirasi 2017-1dewidera27Belum ada peringkat
- PX FisikDokumen178 halamanPX FisikLilia Nur Rahmawati SBelum ada peringkat
- ENDOKRINDokumen30 halamanENDOKRINJulia MujahadahBelum ada peringkat
- (INSTRUKTUR MAHASISWA) Manual CSL Sistem Onkologi 2021-2022Dokumen43 halaman(INSTRUKTUR MAHASISWA) Manual CSL Sistem Onkologi 2021-2022Rahdan NurBelum ada peringkat
- Panduan Praktikum Patologi Klinik Semester 5 Blok Urology Nephrology 6Dokumen31 halamanPanduan Praktikum Patologi Klinik Semester 5 Blok Urology Nephrology 6indahpratiwi.zhaa11Belum ada peringkat
- Buku Panduan Mahasiswa CSL 5 2018-2019Dokumen222 halamanBuku Panduan Mahasiswa CSL 5 2018-2019FK UnilaBelum ada peringkat
- Dokumen - Tips Buku Panduan Kerja Modul Kepaniteraan Klinik Ilmu Bedah Kepaniteraan BedahpdfDokumen70 halamanDokumen - Tips Buku Panduan Kerja Modul Kepaniteraan Klinik Ilmu Bedah Kepaniteraan BedahpdfanthysekarBelum ada peringkat
- Modul Skill Lab 4.3 2020Dokumen94 halamanModul Skill Lab 4.3 2020fani nadilaBelum ada peringkat
- Manual Aseptik 2019Dokumen25 halamanManual Aseptik 2019Muhamad MabruriBelum ada peringkat
- Pemeriksaan Sistem KardiovaskulerDokumen31 halamanPemeriksaan Sistem KardiovaskulerVicky Mbeng100% (1)