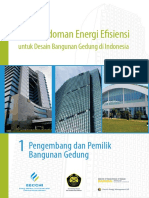Audit Energi CPO PDF
Audit Energi CPO PDF
Diunggah oleh
raymond tambunan0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
49 tayangan128 halamanJudul Asli
Audit Energi CPO.pdf
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
49 tayangan128 halamanAudit Energi CPO PDF
Audit Energi CPO PDF
Diunggah oleh
raymond tambunanHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 128
¥/TA
2002
0005
AUDIT ENERGI PADA PRODUKSI
CRUDE PALM OIL (CPO) DI PTP. NUSANTARA VIL (PERSERO)
UNIT USAHA REJOSARI - LAMPUNG SELATAN
Oleh
TEDI ALI RAHMAT
F01497012
2002
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya
malam dan siang terdepat tanda-tanda bagi orang yang berakal”
(QS: Ali Imran :190)
Rahasia sukses adalah tiadanya ikatan dengan hasil ~ melakukan yang terbaik
di woktu itu dan membiarkan hasil datang dengan sendirinya
Kupersembahkan karye kecil
ini untuk kedue orang tua dan adikku
yang selalu memberikan doa, kasih seyang,
‘motivasi dan pengorbanan
Tedi Ali Rabmat, F01497012. Audit Energi Pada Produksi Crude Palm Oil (CPO)
di Unit Usaha Rejosari PTP. Nusantara VI (Persero) Lampung Selatan. Di bawah
bimbingan Ir. Sti Endah Agustina, MS.
RINGKASAN
Audit energi diperlukan guna mengetahui Kebutuhan energi dan tingkat
effisiensi penggunaannya pada suani proses produksi, Selanjutnya data audit dapat
digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan proses produksi guna meningkatkan
aya saing produk serta untuk perencanaan pengembangan sistem produksi.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit energi pada produksi CPO di
Unit Usaha Rejosari PIP. Nusantara VI (Persero) Lampung Selatan, Sasaran
penelitian ini adalah mengetahui kebutuhan energi untuk menghasilkan tiap ke CPO,
mengetahui aliran energi pada proses produksi CPO tersebut, mengetahui jenis, jumlah
dan sumber energi pada tiap tiep tahapan proses produksi serta mengidentifikasi tahapan
proses yang kurang effisien sehingga usaha penghematan dapat segera dilakukan. Hasil
penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian pada jenis komoditi yang sama
dengan lokasi yang berbeda untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengeruh terhadap
penggunaan energi.
Dari hasil perhitungan terhadap konsumsi energi, baik terhadap energi langsung
‘maupun tidak langsung dengan tidak memperhitungkan masukan energi dari pestisida,
baban kimia pembantu dan alat atau mesin yang digunakan, dibutuhkan masukan energi
primer rata-rata sebesar 15,7550 MJ untuk memproduksi tiap kg CPO pada kapasitas
pengolahan 25 ton TBS/jam dengan tingkat rendemen 20.89 %,
Konsumsi energi primer yang diperlukan tersebut berasal dari input energi
pupuk sebesar 4.925 MJ (31.26 % dari total masukan energi primer), solar 0.7190 MI
(4.57 %), biomassa 9.9200 MJ (62.96 %) dan energi biologis manusia sebesar 0.1900
‘MY (1.20%). Berdasarkan tahapan proses produksi, jumlah energi primer tersebut
dibutuhkan pada kegiatan budidaya sebesar 5.1287 MJ (32.56 % dari total konsumsi
energi primer), pemanenan sebesar 0.0280 MI (0.19 %), pengangkutan 0.2186 MI
(1.40 %) dan pengolahan TBS serta sarana pendukung sebesar 10.3739 MI (65.85 %).
Konsumsi energi pada pengolahan TBS dan sarana pendukung produksi setelah
cnergi primer dikonversikan menjadi energi listrikc yaitu masing-masing sebesar 0.2575
Mirkg CPO dan 0.1820 Mi/kg CPO.Pada pengolahan TBS menjadi CPO, input energi
terbesar berasal dari energi listrik sebesar 0.2530 Mi/kg CPO atau 96.02 % dari total
input energi untuk pengolahan sedangkan tahapan yang paling besar mengkonsumsi
‘nergi yaitu tahapan pengolahan biji sebesar 0.1076 MI/kg CPO atau 43.11 % dari total
konsumsi energi untuk pengolahan TBS menjadi CPO.
Dari aliran energi pada sarana pendukung penyediaan energi didapatkan
effisiensi rill boiler sebesar 74.67 %, effisiensi riil generator diesel sebesar 27.44 %,
effisiensi rl turbin uap untuk menghasilkan energi listrik sebesar 3.82 %. Sedangkan
effisiensi teknis alat yang merupakan perbandingan antara kapasitas terukur dengan
kapasitas terpasang didapatkan effisiensi teknis generator diesel sebesar 42.92 %,
cfisiensi teknis turbin uap sebesar 54.74 % dan effisiensi teknis rata-rata motor listrik
sebesar 73.65 %.
Energi listrik yang dihasilkan dari sarana pendukung penyediaan energi sebesar
0.4277 Mi/kg CPO berasal dari turbin uap sebesar 0.31494 MI/kg CPO. atau 73.63 %
dari total masukan energi listrik dan dari generator diesel sebesar 0.1128 MI/kg CPO
atau 26.37 %. Konsumsi energi listrik pada instalasi pengolahan sebeser 0.2531 MI/kkg,
CPO dan pada instalasi sarana pendukung sebesar 0.1438 MJ/kg CPO, sehingga rasio.
penggunaan energi listrik antara instalasi pengolahan dengan sarana pendukung sebesar
63.76 berbanding 36.24. Kehilangan energi listrik dari input listrik ke peralatan
pengguna listrik sebesar 0.0379 MJ/kg CPO atau sebesar 7.19 % dari total masukan
energi listrik.
Besamya pemborosan energi yang terjadi yaitu sebesar 1.9816 Mi/kg CPO atau
dalam bentuk biaya yaitu Rp. 6.82 /kg CPO sehingga biaya yang terbuang. tiap hari
sebesar Rp. 472475.18. Pemborosan ini berasal dari pemakaian tenaga manusia untuk
pengolahan TBS, penggunaan serat dan cangkang sebagai bahan bakar pada boiler serta
adanya kehilangan energi listrik,
‘Usaha konservasi energi yang dapat dilakukan yaitu pertama, dengan semakin
meningkatkan produksi TBS sehingga kapasitas rill pengolahan tiap hari bisa
bertambah. Kedua, melalui pengaturan konsumsi biomassa sebagai bahan bakar boiler
sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, melalui pembenahan instalasi listrik, memodifiksi
peralatan dan mesin produksi yang bekerja di bawah standar. Keempat, melalui
perbaikan instalasi pipa penyaluran uap yang mengalami kebocoran dan penggunean
uap sesuai kebutuhan, Dalam Konservasi energi ini usaha yang terpenting yaitu
pemahaman operator dalam bekerja tentang pentingnya usaha penghematan energi, serta
upaya perawatan dan pemeliharaan harus terus dilakukan secara kontinyu.
AUDIT ENERGI PADA PRODUKSI
CRUDE PALM OIL (CPO) Di PTP. NUSANTARA VII (PERSERO)
UNIT USABA REJOSARI - LAMPUNG SELATAN
SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknologi Pertanian
Pada Jurusan Teknik Pertanian
Fakultas Teknologi Pertanian
Institut Pertanian Bogor
Oleh
TEDI ALI RAHMAT
F01497012
2002
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
_—————
AUDIT ENERGI PADA PRODUKSI
CRUDE PALM OIL (CPO) DIPTP. NUSANTARA VII (PERSERO)
UNIT USAHA REJOSARI - LAMPUNG SELATAN
SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknologi Pertanian
Pada Jurusan Teknik Pertanian
Fakultas Teknologi Pertanian
Institut Pertanian Bogor
Oleh
Tedi Ali Rahmat
F01497012
Dilahirkan pada tanggal 02 November 1979
di Sukabumi
Tanggal lulus 28 November 2001
Disetujui,
Januari 2002
KATA PENGANTAR
Paji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
Skripsi ini merupakan hasil penelitian di UU Rejosari PTP. Nusantara
VII (Persero). Kajian pokok skripsi ini yaitu audit energi dari mulai tahapan
budidaya kelapa sawit sampai pengolahan TBS menjadi CPO dengan sarana
pendukungnya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknologi Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Bogor.
Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada :
1. Kedua orang tua dan adik Penulis atas segala doa dan motivasinya.
2. Ibu Ir. Sri Endah Agustina, MS., selaku dosen pembimbing yang telah banyak
memberikan bimbingan dan arahan selama Penulis menempuh pendidikan
terutama dalam penyelesaian skripsi ini
3. Bapak Ir. Sunaryanto Purwo selaku Administratur UU Rejosari yang telah
memberikan izin lokasi penelitian,
4, Bapak Agus Faroni, SP., Ir. Hario Wibowo, Ibu Retno Widowati SP., Bapak
Beben Sumadilaga, Bapak EG. Sudarsono, Bapak TB. Simatupang dan Bapak
Hadi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penelitian,
5. Pimpinan beserta staf Yayasan Arzak Dharma Kencana yang telah
memberikan bantuan beasiswa pendidikan dan penelitian,
6. Dr. Ir. Edy Hartulistiyoso M.Sc. dan Dr. Ir. Suroso M.Agr sebagai dosen
penguji.
7. Keluarga Bapak Sukur dan Bapak Dace yang telah memberikan tempat tinggal
selama Penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Agus, Ferly dan Nunu atas kebersamaannya selama penelitian.
9. Keluarga besar TEP-34 atas kekeluargaan dan kekompakannya.
10. FKMPJ Bogor , CAD dan X-Ber members untuk persahabatannya
Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat
tethadap pengembangan ilmu khususnya pada bidang pemanfaatan energi dalam
industri pertanian. Amin,
Bogor, November 2001
Penulis
DAFTAR ISL
KATA PENGANTAR.
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR..
DAFTAR LAMPIRAN...
DAFTAR ISTILAH..
I. PENDAHULUAN..
A, Latar Belakan;
B. Tujuan Penelitian ..
IL TINJAUAN PUSTAKA.
A. Tanaman Kelapa Sawit
B. Proses Produksi CPO...
C. Kebutuhan Energi Dalam Industri dan Pertanian
1. Energi Langsung,
2. Energi Tidak Langsung.
3, Energi Biologis Dari Tenaga Manusia .
D, Masukan Energi Dalam Proses Produksi CPO
E, Audit Energi
Ill. SISTEM PRODUKSI CPO DI UU REJOSARI
‘A. Budidaya Kelapa Sawit
B. Pemanenan....... fenetheeatase . wee 29
C. Pengangkutan Buah...
D. Pengolahan TBS ...
E, Sarana Pendukung
IV. METODOLOGI PENELITIAN.....
A, Waktu dan Tempat....
B. Bahan dan Alat 0.00
C. Pendekatan Masalah dan Batasan Sistem
D, Metode Audit Energi,
E. Parameter Yang Diukur.
F. Metode Pengumpulan Data...
G. Perhitungan dan Analisa Data..
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.
A. Konsumsi Energi Pada Proses Produksi CPO Di UU Rejosari
1. Tenaga Manusia
2. Pupuk
3. Bahan Baker Minyak (Solar)
4. Pestisida
5, Bahan Kimia Pembantu
6. Listr
7. Biomassa
8. Aliran Energi Pada Stasiun Penyediaan Energi
9. Pengeringan di Nut Silo dan Kernel Sil.
B. Peluang Penghematan dan Konservasi Energi
VI. KESIMPULAN...
DAFTAR PUSTAKA.
LAMPIRAN...
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Produksi CPO Indonesia ...
Tabel 2. Input Energi Behan Bakar Untuk Proses Produksi Pertanian
Tabel 3. Nilai Energi Per Unit Beberapa Jenis Bahan Bakar
Tabel 4. Masukan Energi Produksi Bahan Baku dan Pabrikasi dari
Beberapa Alat dan Mesin Pertanian.
Tabel 5. Masukan Energi Untuk Pupuk Nitrogen..
Tabel 6. Masukan Energi Untuk Pupuk Fosfat dan Pupuk Kalium
Tabel 7. Input Energi Untuk Memproduksi Beberapa Jenis Pestisida...
Tabel 8. Nilai Embodied Energy Dari Beberapa Bahan Kimia
Tabel 9. Kebutuhan Bnergi Tenaga Manusia untuk Melakukan
Aktivitas Pada Beberapa Kondisi Beban Kerja...
Tabel 10. Kebutuhan Energi Biologis (Manusia) pada Beberapa
Kegiatan Pertania
Tabel 11. Standar Tingkat Kematangan Bua
Tabel 12. Konsumsi Energi Primer Pada Produksi CPO di UU Rejosari
Tabel 13. Konsumsi Energi Pada Setiap Tahapan Produksi CPO
Di UU Rejosati Setelah Biomassa dan Solar Pada Penyediaan
Energi Dikonversi Menjadi Listrik
Tabel 14. Konsumsi Energi Pada Kegiatan Budidaya ..
Tabel 15. Konsumsi Energi pada Kegiatan Pengolahan TBS menjadi CPO....
Tabel 16. Konsumsi Bnergi Pada Sarana Pendukung ..
Tabel 17. Konsumsi Energi Manusia Pada Setiap Tahapan Produksi . 62
Tabel 18. Konsumsi Energi Pupuk Pada Kegiatan Budidaya.. 64
Tabel 19. Penggunaan Energi Pupuk Untuk Masing-masing jenis
Pupuk yang Digunakan .. . 64
Tabel 20. Konsumsi Energi Solar... . 65
Tabel 21. Konsumsi Pestisida dalam Kegiatan Budidaya... 66
Tabel 22. Konsumsi Bahan Kimia Pembantu... . 67
Tabel 23. Konsumsi Energi Listrik.......
Gambar 1.
Gambar 2,
Gambar 3.
Gambar 4.
Gambar 5.
Gambar 6.
Gambar 7.
Gambar 8.
Gambar 9.
Gambarl0.
Gambar 11.
Gambar 12.
Gambar 13.
DAFTAR GAMBAR
Sistem Produksi CPO. 4
Kegiatan Budidaya Kelapa Sawit . 4
Skema Umum Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi CPO 7
Bagan Alir Proses dan Masukan Energi pada
Produksi CPO di Perksebunan Kelapa Sawit Kertajaya...
Bagan Alir Proses dan Masukan Energi pada
Produksi CPO di UU Beksi PTPN VIII ..
Tahapan Kegiatan Budidaya Kelapa Sawit
i UU Rejosari PTPN VIL
‘Bagan Alir Pengolahen Kelapa Sawit Di UU Rejosari
Aliran Bahan Pada Alat Pengolah Kelapa Sawit Menjadi CPO
Batasan Sistem Yang Akan Diaudit
Bagan Alir Proses dan Masukan Energi Pada Produksi CPO
di UU Rejosari PTPN VIL.
Bagan Alir Penelitian..
Aliran Energi Pada Produksi CPO di UU Rejosar'....
Aliran Energi Pada Stasiun Penyediaan Energi.
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Peta Lokasi Perkebunan UU Rejosari PTPN. VIL.
Lampiran 2. Produktivitas TBS Selama Umur Produktif.
Lampiran 3. Bagen Alir Pengolahan di UU Rejosari
Lampiran 4. Data Produksi CPO...
Lampiran 5. Data Waktu Pengolaban ..
Lampiran 6, Konsumsi Energi Pada Pembibitan Pre Nurser)
Lampiran 7. Konsumsi Bnergi Pada Pembibitan Main Nursery...
Lampiran 8. Konsumsi Bnergi Pada Persiapan Lahan.
Lampiran 9. Konsumsi Energi Pada Persiapan Tanam dan Penanaman.....
Lampiran 10. Konsumsi Energi Pada Pemeliharaan TBM.....
Lampiran 11, Konsumsi Energi Pada Pemeliharaan TM...
Lampiran 12. Konsumsi Energi Pada Pengangkutan TBS. :
Lampiran 13. Konsumsi Energi Pada Pengolahan TBS Menjadi CPO
Lampiran 14. Konsumsi Energi Pada Sarana Pendukung
Lampiren 15, Konsumsi Energi Listrik.
Lampiran 16. Hasil Pengamatan Pada Generator Diesel ..
Lampiran 17. Data Hasil Pengamatan Untuk Sistem Boiler.. servers 104
Lampiran 18. Contoh Perhitungan Untuk Penentuan Konsumsi Bahan
Bakar Teoritis...
Lampiran 19. Data Hasil Pengamatan dan Pengukuran Pada Pengeringan
Lampiran 20. Contoh Perhitungan Pada Proses Pengeringan
Lampiran 21. Perhitungan Pemborosan Energi...
Lampiran 22. Tabel Uap Superheated.
Lampiran 23. Tabel Uap Saturated.
Lampiran 24. Psychometric Chart.
DAFTAR ISTILAH
A. Istilah Lokal
ALB
Bedengan
Bokoran
Brondolan
Dodos
Egrek
Gawangan
HOK
Kastrasi
Menumbang
Menunas
Merumpuk
PKS
TBM
TBS
™
TPH
uu
: Asam Lemak Bebas
: Tempat untuk meletakan polybag pada pembibitan pre mursery
: Pembersihan tanah sekitar pokok tanaman
: Buah Kelapa sawit yang terlepas dari tandannya
: Alat panen kelapa sawit sejenis linggis bermata lebar
: Alat panen kelapa sawit berupa sabit bergagang bambu panjang
: Daerah antar barisan kelapa sawit
: Hari Orang Kerja
: Memotong bunga jantan dan bunga betina
: Membongkar tanaman kelapa sawit asal
: Memotong pelepah kelapa sawit
: Mengumpulkan batang kelapa sawit yang telah dibongkar
: Pabrik Kelapa Sawit
: Tanaman Belum Menghasilkan
: Tandan Buah Segar
: Tanaman Menghasilkan
: Tempat Pengumpulan Hasil
: Unit Usaha
B. Istilah Asing
Boiler
BPV
Conveyor
cro
Fiber
Kernel
Main nursery :
Nut
PKO
Polybag
: Ketel uap
: Back Pressure Vessel (tangki tekanan balik)
: Rantai berjalan yang digerakan oleh motor listrik
: Crude Palm Oil (minyak kelapa sawit mentah)
: Serat
: Inti kelapa sawit
Pembibitan utama
: Biji kelapa sawit
: Palm Kernel Oil (minyak inti kelapa sawit)
: Plastik berwamna hitam sebagai media tanam pembibitan
Pre Nursery
Replanting
Saturated steam
Selective weeding
Shell
Sludge
Superheated steam
Steam
Top soil
Wiping
: Pembibitan awal
: Tanam ulang sebagai upaya peremajaan_
: Uap jenuh
: Pembersihan areal secara selektif|
: Cangkang
: Limbah padat berupa lumpur dari proses pemurnian
minyak
: Uap super jenuh,
: Uap panas
: Tanah lapisan atas
: Pemberantasan ilalang dengan cara diusap dengan
herbisida.
vii
i, PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peningkatan jumlah penduduk serta standar hidup masyerakat, akan
meningkatkan permintaan barang pemuas kebutuhan dan konsumsi energi. Hal
ini akan berimbas tethadap dunia industri dalam artian industri dituntut semakin
meningkatkan jumlah produksinya. Ini berkaitan erat dengan biaya yang harus
dikeluarkan, Salah satu faktor yang mempengaruhi biaya produksi yaitu jumlah
pemakaian energi. Di lain pihak industri berusaha untuk menurunkan biaya
produksinya agar dapat bersaing di pasaran. Oleh karenanya upaya peningkatan
efisiensi penggunaan energi merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan.
Penggunaan energi secara efisien merupaken saleh satu usaha
penghematan energi yang hasilnya dapat dirasakan dalam waktu relatif singkat,
Audit energi merupakan suatu langkah awal dalam pelaksanaan program
konservasi energi. Audit energi bertujuan untuk mempelajari penggunaan energi
pada suatu proses produksi yang meliputi jumlah, jenis dan sumber energi,
aliran energi, dan biaya energi. Sehingga hasil audit energi dapat dijadikan
sebagai acuan bagi perusahaan untuk membantu menentukan strategi yang tepat
untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan salah satu
hasil pengolahan Kelapa sawit. CPO digunakan untuk bahan baku berbagai
industri diantaranya industri pangan, industri sabun, industri baja, industri
tekstil dan industri kulit. Beragamnya industri yang menggunakan bahan CPO
tersebut akan meningkatkan permintaan terhadap CPO.
Sesuai dengan rekomendasi Bank Dunia, untuk memberikan_prioritas
yang tinggi bagi pengembangan tiga tanaman keras yaitu karet, kelapa dan
kelapa sawit, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan lahan bagi
pengembangan ketiga jenis tanaman tersebut dalam skala besar. Alokasi Iahan
terluas yaitu 2830 ribu hektar atau 68.2 % dari total Iuas alokasi lahan bagi
ketiga tanaman tersebut di atas digunakan untuk tanaman kelapa sawit (Bank
Bumi Daya, 1988). Dengan demikian basil dari perkebunan kelapa sawit
berupa TBS akan semakin meningkat. Meningkatnya produksi TBS berarti
meningkatnya juga produksi CPO. Peningkatan produksi CPO dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Produksi CPO Indonesia
TABUN PRODUKSI CPO (Ton)
1990 2412612
1991 2657600
1992 3266250,
1993 3421449
1994 4008062
1995 4479670,
1996 4959759
1997 5356541
1998, 5487635,
1999 5276483
2000 5541678
‘Sumber: Biro Pusat Statistik, 2007.
Meningkatnya permintaan terhadap CPO, menyebabkan proses,
produksi untuk menghasilkan CPO menjadi berkembang. Dalam hal ini proses
produksi tersebut tentunya harus beroperasi dengan optimal untuk meneapai
produktivitas yang tinggi agar dapat mengimbangi laju permintaan tethadap
CPO dan juga agar produknya bisa bersaing di pasaran. Salah satu upaya yang
dilakukan yaitu mengurangi biaya energi melalui penggunaan energi secara
efisien dan usaha tersebut dapat dilakukan dengan audit energi.
B. Tujuan Penelitian
‘Tujuan penelitian ini yaitu melakukan audit energi pada proses produksi
CPO di Unit Usaha Rejosari PTP. Nusantara VII (Persero) Lampung Selatan.
Keluaran yang diinginkan adalah :
1. Jumlah kebutuhan energi untuk memproduksi satu kilogram CPO.
2. Mengetahui aliran energi pada proses produksi CPO tersebut.
3. Mengetahui jenis, jumlah dan sumber energi pada tiap tahapan proses
produksi.
4. Mengidentifikasi tahapan proses produksi yang kurang effisiéh sehingga
usaha penghematan dapat segera dilakukan.
I, TINJAUAN PUSTAKA
A. Kelapa Sawit
Tanaman kelapa sawit (Blais Guinensis Jacq) merupakan tumbuhan
tropis yang tergolong dalam famili palae. Dewasa ini tanaman kelapa sawit
tersebar di sepanjang daerah tropis, terutama di kawasan yang terletak antara
15° Lintang Utara sampai 15° Lintang Selatan dengan subu rata-rata 24°C
sampai 30° C, dimana fluktuasi suhu kurang dari 10° C (Setyamidjaja,1991).
Tanaman kelapa sawit menghendaki keadaan topografi berbentuk
dataran landai, dengan ketinggian sampai sekitar 500 meter di atas permukaan
laut, pH tanah sekitar 4 - 6. Curah hujan yang diperlukan berkisar 2000 mm
sampai 3000 mm per tahun yang tersebar merata sepanjang tahun, kelembaban
udara antara 50% - 90% dan lamanya penyinaran (cahaya matahari) antara 5
jam sampai 7 jam setiap hari. Kelapa sawit dapat tumbuh tegak lurus
mencapai ketinggian 15 m~20m. Kelapa sawit mulai menghasilkan pada
umur sekitar 30 bulan setelah tanam. Kelapa sawit biasanya sudah tidak
produktif lagi pada wnur lebih dari 25 tahun (Setyamidjaja, 1991).
B. Proses Produksi CPO
Proses produksi CPO merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai
dari budidaya di kebun sampai pengolahan TBS di pabrik dengan di tunjang
aspek pendukungnya, Proses produksi ini ditujukan untuk menghasilkan
sebanyak mungkin CPO dengan tetap memperhatikan standar mutu produk.
Upaya ini dilakukan melalui pengembangan tanaman kelapa sawit melalui
budidaya dengan orientasi meningkatkan produksi Tandan Buah Segar (TBS).
Upaya lain dilakukan di pabrik pengolahan Kelapa sawit dengan upaya
meningkatkan effisiensi proses. Proses produksi CPO akan berjalan dengan
optimal jika ditunjang dengan sarana pendukungnya. Sistem produksi
merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jika salah satu tahapan
atau kegiatan mengalami gangguan maka kegiatan lainnya akan terganggu
(Rahmat, 2001).
Sistem produksi CPO dapat dilihat pada Gambar 1
Budidaya kelapa sawit kK
Pemanenan J
Pengangkutan buah
)
Pengolahan kelapa sawit menjadi CPO
Penyimpanan CPO
Gambar 1. Sistem Produksi CPO (Rahmat, 2001)
1, Budidaya Kelapa Sawit
Pembudidayaan kelapa sawit dimaksudken ager hasil yang diperoleh
dari tanaman tersebut menjadi lebih tinggi dan bermanfeat. Pemungutan hasil
kelapa sawit yang tumbuh secara alami/liar tidak dapat diharapkan memberikan
hasil yang tinggi dan oleh sebab itu dilakukan pembudidayaan tanaman tersebut
(Bank Bumi Daya, 1988). Budidaya tanaman kelapa sawit meliputi kegiatan
pembukaan dan persiapan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan.
Budidaya kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 2.
Pembukaan dan_persiapan lahan
4
Pembibitan
Penanaman
1
Pemeliharaan
Gamber 2. Kegiatan Budidaya Kelapa Sawit
a. Pembukaan dan persiapan Iahan
Cara pembukaan dan persiapan tergantung kondisi lahan yang akan
ditanami. Cara pertama dilakukan untuk Jahan hutan atau semak belukar, cara
ini disebut sebagai bukaan baru (new planting). Cara kedua dilakukan untuk
lahan yang sebelumnya ditanami komoditi perkebunan lain misainya karet atau
kopi. Cara ketiga yaitu untuk mengganti tanaman kelapa sawit yang sudah
tidak produktif cara ini disebut sebagai upaya peremajaan (replanting)
Pembukaan dan persiapan lahan dapat dilaksanakan secara mekanis,
kimia, maupun manual. Pelaksanaan persiapan lahan untuk penanaman
dilakukan melaiui beberapa tahap yaitu survei areal, pembersihan Jahan (land
clearing), pengolahan tanah, pemancangan, pembuatan lubang tanam dan
pembuatan saluran drainase serta pembuatan teras (Anonimous, 1993).
b. Pembibitan
Proses pembibitan dilakukan melalui dua tahap yaitu pembibitan awal
(pre nursery) selama 3 bulan dan pembibitan utama (main mursery) selama 9
bulan Tahapan pengerjaan yang dilakukan yaitu pemilihan dan persiapan
lahan, pembuatan bedengan, pembuatan naungan, pengisian tanah, penanaman,
pemeliharaan dan pemindahan bibit (Anonimous, 1993).
c. Penanaman
Jarak tanam yang sering digunakan yaitu sistem segitiga sama sisi
dengan ukuran 9 m x 9 m x 9 m dengan populasi tanaman adalah 143 pohon per
hektar. Proses penanaman dimulai dengan pemindahan bibit ke Iubang tanam
yang dilanjutkan dengan menanam tanaman penutup tanah (legume cover
crop/LCC) (Anonimous, 1993).
d. Pemeliharaan
Pemeliharaan dilakukan terhadap tanaman belum menghasilkan
(TBM) dan tanaman menghasilkan (TM). Proses pemeliharaan meliputi
penyulaman, penyiangan, bokoran, pengendalian hama dan -penyakit,
pemupukan, penunasan, kastrasi, inventarisasi tanaman, sanitasi. dan
pemeliharaan jalan, teras serta saluran air (Setyamidjaja, 1991).
2. Pemanenan
Pemanenan meliputi pekerjaan memotong tandan buah matang,
memungut tandan dan buah yang lepas dari tandan (brondolan) serta
pengangkutan ke tempat pengumpulan hasil (TPH). TM dapat dipanen apabila
60% atau lebih buahnya telah matang panen. Waktu panen ditentukan oleh
rotasi_panen, yaitu rentang waktu antara panen pertama dengan panen
berikutnya pada blok yang sama, Kematangan buah tampak dari kulit buah
yang berwama merah jingga dan jumlah brondolan yang jatuh di sekitar pokok
tanaman, Peralatan panen utama yang digunaken untuk ketinggian tanaman
2m-5 m yaitu kapak dan dodos/chise! semacam tombak bermata lebar. Untuk
ketinggian lebih dari 5 m digunakan egrek berupa sabit bergagang bambu
panjang (Anonimous, 1993).
3. Pengangkutan Buah
Tandan dan brondolan yang jatuh diangkut dan dikumpulkan di TPH.
Buah yang terkumpul harus segera diangkut pada hari itu juga, untuk
menghindari peningkatan kadar asam lemak bebes. Pengangkutan buah
dilakukan dengan menggunakan mobil, traktor maupun lori angkut, Jenis alat
angkut yang digunakan tergantung kondisi lahan (Sholahuddin, 1999).
4, Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi CPO
Pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dimaksudkan untuk
mendapatkan CPO sebanyak mungkin. Lokasi pabrik pengolahan_ terletak
dekat dengan perkebunan untuk memudahkan pengangkutan bush ke pabrik,
dekat dengan sumber air untuk keperluan pabrik namun bebas dari gangguan
banjir, serta terletak pada daerah yang memungkinkan untuk perluasan
pabrik/peningkatan kapasitas pabrik. (Setyamidjaja,1991)..
Pengolahan Kelapa sawit menjadi CPO dilakukan melalui
beberapa tahap yaitu penerimaan TBS, perebusan, penebahan, pelumatan,
pengempaan, pemumian minyak, pengeringan dan pemecahan biji (Bank Bumi
Daya,1988). Pengolahan kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 3.
Penimbangan
¥
Penimbunan buah sementara
Perebusan
Penebahan
{
Pelumatan
{
Pengempaan
— _
Pengeringan dan pemecahan biji Pemurnian minyak
1 Y
Pabrik inti Penyimpanan CPO
Gambar 3. Skema Umum Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi CPO (Bank Bumi
Daya,1988)
a, Penerimaan Buah
Untuk menghindari terbentuknya asam lemak bebas (free fatty acid)
pengolahan harus dilaksanakan paling lambat jam setelah panen. Buah yang
masuk ditimbang dan ditampung sementara di loading ramp. Dengan
membuka pintu-pintu loading ramp, buah akan masuk secara mudah ke lori-lori
rebusan, (Rahmat, 2001).
b. Perebusan
Buah beserta lorinya direbus dalam tempat rebusan dengan
mengalitkan/menekankan wap panas selama 90 menit ke dalam tempat rebusan
tersebut, Suhu uap yang digunakan adalah 130° C dan tekanan dalam ruang
perebusan + 2,5 Kem? (Setyamidjaja,1991).
c. Penebahan
Proses ini bertujuan untuk memisabkan buah dari tandannya. Alat
yang digunakan yaitu auto feeder dan thresser. Prinsip penebahan yaitu
dengan membanting buah dalam drum yang berputar. Bagian dalam drum
berbentuk kisi, sehingga buah yang sudah terpipil akan lolos ke bawah,
sedangkan tandan kosong akan terdorong ke luar (Setyamidjaja, 1991).
d. Pelumatan
Pelumatan merupakan proses untuk menghancurkan bush sehingga
memudahkan pengeluaran minyak pada proses pengempaan. Proses terjadi di
digester dimana buah dilumatkan dengan bantuan panas dan pisau perajang
yang sekaligus berfungsi sebagai pengaduk. Proses pelumatan berlangsung 30
menit sampai 45 menit dengan suhu 90° C. (Naibabo, 1992).
ce. Pengempaan
Ada bermacam-macam cara untuk mengeluarkan minyak (extraction of
oil). Cara yang umum digunakan adalah pengempaan dengan menggunakan
alat pengempa tipe hydraulic, centrifugal atau tipe continous screw press
(Naibaho, 1998). Daging buah yang sudah dilumatkan di mesin pelumat,
dimasukan ke dalam alat pengempa kemudian dikempa sehingga minyak dapat
dikeluarkan dan dipisahkan dari ampasnya. Minyak yang keluar ditampung
untuk selanjutnya dimumikan, Sedangkan ampasnya keluar secara terpisah dan
dipergunakan sebagai bahan bakar untuk boiler (Naibaho, 1992).
£. Pemumian minyak
Minyak yang keluar dari pengempa mengandung 45 % sampai 55 %
air, Jumpur dan bahan-bahan lainnya, Dalam cairan minyak hasil pengempaan
terdapat beberapa fase yang sulit dipisahkan dengan satu cara, sehingga
dilakukan pemisahan minyak, padatan dan air dengan beberapa tahapan.
Tahapan pemisahan dalam pemurnian ini meliputi filtrasi, pengendapan,
penguapan, sentrifugasi dan pengeringan. (Naibaho, 1998). Minyak yang sudah
dikeringkan_mempunyai kadar air kurang dari 0.1 % (Naibaho, 1992).
g. Pengeringan dan Pemecahan Inti
Ampas pengempaan yang berupa serat dan biji, masuk ke alat pemisah
serat dengan biji yaitu depericarper yang bekerja berdasarkan hisapan angin
dari blower. Untuk menghilangkan serat yang masih menempel di biji
dilakuken di polishing drum, dengan cara biji masuk dalam drum yang
berputar sehingga terjadi gesekan antara biji dengan permukaan drum. Biji yang
telah terpisah kemudian dikeringkan di nut silo selama kurang lebih 18 jam,
dan setelah itu biji yang telah kering akan dipecahkan. Proses pemecahan biji
berlangsung di mut cracker melalui mekanisme bantingan atau berlangsung di
ripple mill melalui mekanisme penggilasan. (Naibaho, 1998). Biji yang sudah,
dipecah keluar dalam bentuk cangkang dan inti lalu dipisahkan melalui
separating coloum dengan mekanisme pemisahan berdasarkan hisapan angin.
Kemudian inti dikeringkan di kernel silo yang berlangsung selama kurang
Jebih 12 jam. Inti yang telah dikeringkan alu masuk ke tempat penyimpanan
inti, Cangkang yang keluar dari separating coloum digunakan sebagai bahan
bakar untuk boiler.
h, Penyimpanan CPO
Minyak yang telah dikeringkan berupa minyak mentah (CPO)
kemudian disimpan dalam tangki timbun (storage tank). Suhu dalam tangki
dipertahankan sekitar 45 °C untuk mencegah terjadinya penggumpalan.
Sumber panas untuk mempertahankan sulu berasal dari pipa yang berisi steam
(Anonimous, 1993).
5. Sarana Pendukung Proses Produksi
Untuk menunjang kelangsungan proses produksi CPO diperlukan
berbagai sarana pendukung. Sarana tersebut yaitu penyediaan air, penyediaan
energi, dan penanganan limbah. Semua sarana tersebut tidak bisa terpisah dari
proses produksi. Salah satu sarana mengalami gangguan maka proses produksi
dan aspek lain akan terganggu juga.
‘©
a. Penyediaan Air
Air merupakan bagian penting untuk menunjang proses produksi.
Menurut Naibaho, (1998) kebutuhan air untuk pengolahan kelapa sawit yaitu
0.6 m°/ton TBS dan untuk umpan boiler sekitar 0.6m°/tonTBS, sehingga air
yang dibutubkan yaitu 1.2 mon TBS. Air yang diperlukan tersebut berasal
dari sungai atau danau yang dipompa ke pabrik pengolahan. Air yang akan
digunakan untuk pengolahan belum memenuhi syarat jika langsung digunakan
untuk pengolahan, schingga diperlukan adanya penanganan (treatment) terlebih
datulu (Naibaho,1998).
b. Penyediaan Energi
Energi utama pada pengolahan kelapa sawit, dibedakan menjadi dua
yaitu energi uap dan energi listrik. Energi uap ini dipasok oleh Doiler
sedangkan energi listrik berasal dari turbin uap dan generator diesel. Uap dari
boiler digunaken untuk menggerakkan turbin, lalu uap ditampung dalam tangki
uap bekas (back pressure vessel = BPV) dan digunaken untuk pengolahan.
Bahan bakar untuk boiler yang digunakan berasal dari cangkang dan serat yang,
merupakan limbah pengolahan (Naibaho, 1998).
3. Penanganan Limbah,
Limbah yang ditangani terbagi dua yaitu limbah padat dan limbah cair.
Limbah padat berupa serat dan cangkang digunakan sebagai bahan bakar untuk
boiter sedangkan tandan Kosong digunakan sebagai pupuk di kebun. Limbah
cair yang terbentuk tiap ton TBS yang diolah yaitu + 600 kg. (Naibaho, 1998).
Menurut Lubis, (1992) tahapan penanganan limbah cair yaitu melalui proses
pendinginan yang berlangsung di kolam pendingin (cooling pond), reaksi
anaerobik yang berlangsung dalam kolam anaerob dan teaksi aerobik yang
berlangsung di kolam aerob. Proses yang terjadi pada kolam anaerob yaitu
penguraian limbah oleh bakteri anaerobik melalui proses _hidrolisa,
pengasaman, pembentukan asam asetat dan gas methan.
C. Kebutuhan Energi Dalam Industri dan Pertanian
Kebutuhan energi dalam bidang industri dan pertanian dapat dibagi
menjadi tiga golongan yaitu energi langsung, energi tidak langsung dan
energi biologis Kkhususnya dari tenaga manusia, Energi tersebut dibutuhkan
sebagai input atau masukan pada proses produksi.
1. Energi Langsung
Energi langsung merupakan energi yang digunakan secara Jangsung
pada proses produksi yaitu berupa bahan bakar fosil (Abdullah, 1998).
Menurut Kitani, (1982) dalam Santoso, (1999) energi langsung merupakan
energi yang digunakan seara Iangsung dalam proses produksi, termasuk di
dalamnya yaitu bahan bakar dan listrik, Peran energi langsung sangat besar
dalam suatu proses produksi, terutama untuk proses produksi yang padat
energi, hal ini terkait dengan kebutuhan listrik dan bahan bakar yang cukup
tinggi.
Jumlah energi bahan bakar yang digunakan untuk beberapa operasi
mekenis pada lahan pertenian dapat dilihat pada Tabel 2, dengan merata-
ratakan antara operasi di tanah ringan dan berat, cuaca basah dan kering serta
tanah datar dan berbukit. Sedangkan nilai energi dari beberapa jenis bahan
bakar dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 2. Input Energi Untuk Beberapa Operasi Pertanian
Operasi Energi (Mi/ha)
Memibajak (kedalaman 0.2 m) 1180
Mengolah tanah tahap kedua 390
Mengolah tanah dengan rotary 1430
‘Mengolah tanah ringan 240
Membuat alur 240
Sumber : Leach (1976) dalam Pimentel (1980)
Input energi listrik merupakan input energi yang penting, terutama
untuk proses produksi yang banyak menggunakan motor listrik. Kebutuhan
terhadap energi listrik pada tiap jenis proses produksi tidak sama , kebutuhan
ini tergantung dari jenis dan peralatan produksi yang digunakan.
‘abel 3. Nilai Energi Per Unit Beberapa Jenis Bahan Bakar
Sumber energi | Unit | Nilai kalor Input Nilai Kalor total
(Mifunit) | produksi (Mi/unit)
(Mi/unit)
Gasolin Liter | 32.24 8.08 40.32
Minyak diesel | Liter | 38.66 9.12 47.78
LPG Liter | 26.10 6.16 32.26
Gas alam mm 41.38 8.07 49.45
Batubarakeras | Kg | 30.23 2.36 32.59
Batubara ringan | Kg 30.29 2.37 32.76
Kayu keras kg 19.26 1.44 20.70
Kayu lunak Kg 17.58 132 18.90
Listrik KWh | 3.60 8.39 11.99
Serat! Kg 11.29 - 11.29
Cangkang" Kg 18.39 - 18.39
Sumber : Cervinka(1980) dalam Indrayana, 2001)
1) : Data diambil dari UU Rejosari PTPN. VII
2. Energi Tidak Langsung
Energi tidak langsung merupakan energi yang digunakan untuk
memproduksi suatu masukan produksi seperti pupuk, pestisida, alat dan
mesin, Jumlah energi langsung dan tidak langsung yang digunakan untuk
memproduksi suatu barang disebut embodied energy. Menurut Doering (1978)
embodied energy adalah energi yang digunakan secara tidak langsung pada
produksi pertanian, dalam hal ini yaitu energi untuk memproduksi mesin,
peralatan, pupuk, pestisida, bangunan dan bahan pendukung lainnya.
Menurut Flicks (1992), embodied energy mengacu pada total energi
yang diperlukan dalam pembuatan suatu barang. Embodied energy
mengandung arti semua jenis energi yang dibutuhkan untuk memproduksi
suatu barang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
a. Energi Peralatan dan Mesin
Menurut Doering III dan C. Otto (1978), tiga Kategori energi yang
dihitung secara terpisah sebelum dikombinasikan untuk menyatakan energi
total yang terkandung dalam suatu alat dan mesin pertanian adalah energi yang
terkandung pada pada suatu alat (embodied energy), energi pabrikasi dan
12
energi perbaikan serta perawatan. Masukan energi produksi bahan baku dan
pabrikasi dari beberapa alat dan mesin pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Masukan Energi Produksi Bahan Baku dan Pabrikasi Dari Beberapa
Alat dan Mesin Pertanian
Kategori energi Masukan energi (MI/kg)
Embodied energy bahan
Ban 85.81
Baja 62.79
Traktor 49.45
Mesin perakit 50.29
Energi pabrikasi
Traktor 14.63
Mesin perakit 13.01
Singkal, piringan 8.63
Chisel 8.35
Alat semprot 1.38
Sumber : Doering IiI dan C. Otto, 1978.
Besamya energi produksi balan baku alat dan mesin pertanian yang
meliputi kegiatan dari penambangan hingga menjadi bahan baku, ditunjukan
pada persamaan :
Epb= mx Cpb een(2el)
dimana :
Epb = Energi produksi bahan baku (MJ)
m= Masse alat atau mesin pertanian (kg)
Cpb= Nilai kalor energi produksi bahan baku alat pertanian (MI/kg)
Disamping energi untuk produksi bahan baku, diperlukan juga energi
pabrikasi dalam pengerjaan dan pembentukan alat atau mesin pertanian yang
ditunjukan oleh persamaan :
Ef=mx Cf seeees(2.2)
dimana:
Ef = Energi pabrikasi (MJ)
m_ = Massa alat atau mesin pertanian (kg)
Cpb = Nilai kalor energi pabrikasi suatu alat/mesin pertanian (MJ/kg)
Menurut Doering II dan C. Otto (1978) energi total produksi alat
atau mesin pertanian diasumsikan sebesar 82 % dari total energi bahan baku
dan pabrikasi. Nilai tersebut diambil sesuai dengan pendekatan umur alat atau
mesin yang dapat dipercaya dan persamaanya dapat ditunjukan sebagai berikcut
Btf= 0.82 x (Epb + Ef) 2.3)
Dimana : Etf = Energi total produksi alat atau mesin pertanian (MJ)
Epb = Energi produksi bahan baku (MJ)
Ef =Energi pabrikasi (MJ)
Besamya energi yang digunakan untuk perbaikan dan perawatan
ditunjukan melalui persamaan : ( Doering I, 1978 dalam Pimentel 1980).
Epr= (Epb + Ef) x TAR x 0.333 ... 2-(24)
dimana :
Epr = Energi perbaikan dan perawatan (MJ)
Epb = Energi produksi bahan baku (MJ)
Ef = Energi pabrikasi (MJ)
TAR=Koefisien perbaikan total akumulasi (%) yaitu merupakan
perbandingan biaya perbaikan dan perawatan akumulasi dengan harga
sebenamya pada umur alat.
Dari persamaan diatas embodied energy alat atau mesin pertanian
merupakan penjumlahan dari total energi produksi dan energi perbaikan serta
perawatan, Nilai embodied energy dapat dilihat pada persamaan
Be=Etf + Epr 2.5)
dimana:
Ee = Embodied energy alat atau mesin pertanian (MJ)
Etf = Energi total produksi alat atau mesin pertanian (MJ)
Epr = Energi perbaikan dan perawatan (MJ)
b. Energi Pupuk
Penentuan jumlah energi yang diperlukan untuk menghasilkan satu
kilogram pupuk relatif sulit dilakukan Karena pupuk yang sama jenisnya, bisa
berupa produk yang berbeda, misalnya pupuk nitrogen, bisa berupa amoniak,
urea atau amonium sulfat, Masukan energi tidak langsung dari pupuk
4
didasarkan pada jumlah energi yang diperlukan untuk memproduksi,
transportasi dan distribusi_ maupun penyimpanan, Masukan energi untuk
beberapa jenis pupuk dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel 5. Masukan Energi Untuk Pupuk Nitrogen
Jenis pupuk Produksi | Transportasi | Distribusi | Total
(Mi/kg) (Mi/kg) (Mi/kg) | (Mi/kg)
‘Anhydrous ammonia | 49.97 0.84 0.42 50.23
Urea 56.93 1.67 1.26 59.86
Ammonium nitrate 58.18 2.09 1.26 61.53
Sumber : Blouin et al.(1975) dalam Pimentel (1980).
Tabel 6. Masukan Energi Untuk Pupuk Fosfat dan Pupuk Kalium
Jenis pupuk Produksi | Transportasi | Distribusi | Total
(Milks) | (Miko) | (Mi/kg) | (MiI/Ke)
Phospate Rock 1.67, - 3.77, 5.44
‘Normal Super Phosphate | 2.51 0.84 6.28 9.63
(0-20-0)
Triple Super Phosphate 9.21 0.84 251 12.56
(0-46-0)
Muriate of Potash 4.60 > 2.09 6.69
(0-60-60) / KCL
Sumber : Blouin et al.(1975) dalam Pimentel (1980).
c. Energi Pestisida
Besarnya masukan energi tidak langsung dari energi pestisida
didasarkan pada besamya energi yang dibutuhkan untuk memproduksi
pestisida tersebut. Masukan energi untuk beberapa jenis pestisida dapat di
lihat pada Tabel 7.
c. Energi Bahan Lainnya
Selain pupuk dan pestisida, dalam industri dan pertanian sering
digunakan beberapa jenis bahan kimia pembantu untuk menunjang proses
produksi. Nilai embodied energy dati beberapa jenis bahan kimia pembantu
dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 7. Input Energi Untuk Memproduksi Beberapa Jenis Pestisida
Jenis Pestisida
Input_energi (Mi/kg)
Herbisida
MCPA 130
24-D 85
245-7 135
Dicamba 295
Chloramben 170
Fluazifob-butyl 518
Propanil 220
Propachlor 290
Chlorsulfuron 365
Butylate 141
Diuron 270
Fluometuron 355
Atrazine 190
Dinoseb 80
Trifuralin 150
Diguat 400
Paraquat 460
Glyphosate 434
Linuron 290
Bentason 434
EPTC 160
Metolachlor 276
Fungisida
Ferban 61
Maneb 99
Captan us
Benomyl 397
Tnsektisida
Methyl parathion 160
Carbofuran 454
Carbaryt 153
Toxaphene 38
Cypermethrin 580
Chlorodimeform 230
Lindane 58
Malathion 229
Parathion 138
Methoxychlor 70
Sumber : Green (1987) dalam Fluck (1992).
16
‘Tabel 8. Nilai Embodied Energy Dari Beberapa Bahan Kimia
Bahan Embodied energy (Milkg)
‘NaOH 1.43
NaCl 1.43
Belerang (SO:) 31.38
C20 130
MgO. 1.32
Na;POa 1.43
Batu kapur 132
Sumber : Pimentel (1980).
3. Energi Biologis Dari Tenaga Manusia
Operasi di bidang pertanian tidak bisa lepas dari peran tenaga manusia,
walaupun mungkin peran tenaga manusia hanya sebagai operator atau tenaga
pembantu, Kebutuhan energi dasar seseorang tergantung ukuran badan, umur,
jenis kelamin, jenis pekerjaan, iklim dan faktor lingkungan lainnya (Callubine,
1950; Quenoville et al, 1951; Sugss &Splinter, 1961 ; FAORWHO 1974,
dalam Abdullah dkk 1998). Menurut Astrand & Rodahl dalam Abdullah
(1998), hanya 20 % - 30 % energi kimia dari makanan dapat dikonversikan
menjadi tenaga mekanis. Untuk kerja sehari penuh, keluaran energi manusia
diperkirakan sekitar 0.1 HP (75 watt atau 1.07 Keal/menit).
Menurut Departemen Mekanisasi Pertanian dalam Sholahuddin
(1999), pengeluaran tenaga manusia secara normal berkisar antara 0.4 — 0.7
kW (setara dengan 1.44 Mi/jam ~ 2.52 Mifjam). Dengan memperhitungkan
waktu istirahat selama 8 jam kerja, maka kebutuhan tenaga manusia sekitar
0.32 kW — 0.35 kW ( setara dengan 1.15 MJ/jam — 1.20 MJ/jam). Wanders
dalam Indrayana (2001) mengemukakan tabel Klasifikasi beban kerja secara
kasar yang disebut skala Chirstensen untuk tenaga kerja berumur 20 tahun —
50 tabun yang dapat dilihat pada Tabel 9. Sedangkan kebutuhan energi
manusia di berbagai kegiatan pertanian dapat dilihat pada Tabel 10 .
Tabel 9. Kebutuhan Energi Manusia untuk Melakukan Aktivitas Pada Beberapa
Kondisi Beban Kerja
Kerja | Kegja | Kerja | Kerja
Aktivitas ringan | sedang | berat | sangat
(MI) (MY) | (Mi) _| berat (vu)
Wanita (berat tubuh 55 kg)
Istirahat (Sjam) 18 18 18 18
Kerja (8 jam) 3.3 42 59 15
Rata-rata/kg berat tubuh 0.15 0.17 | 0.20 0.23
Pria (berat tubuh 55 kg)
Istirahat (8jam) 21 24 21 2.1
Kerja (8 jam) 4.6 58 8.0 10.0
Rata-rata/kg berat tubuh 0.17 0.19 | 0.23 0.26
Sumber : FAO dan WHO, (1974) dalam Indrayana, (2001)
Tabel 10. Kebutuhan Energi Biologis (Manusia) pada Beberapa Kegiatan
Pertanian
Kegiatan Kkal/menit Mijjam
Pra panen
Membersihkan semak 61 1.532
Penanaman 32 0.803
Menyiangi rumput 61 1.532
Pemanenan 49 1.230
Aplikasi pestisida 69 1.733
Pengolahan taneh secara mekanis, 42 1.055
Pengolahan tanah secara manual 69 1.733
Memupuk 69 1.733
Mengukur/merintis 20 0.502
Pembuatan drainase/jalan 61 1.532
Wiping 6.1 1.532,
Pasca panen
Pengolahan di pabrik 14 0.725
Sumber : Stout (1990),
D. Masukan Energi Dalam Proses Produksi CPO
Pada proses produksi CPO masukan energi dibedakan menjadi tiga
bagian yaitu energi langsung, energi tidak lagsung dan energi biologis
Knususnya dati tenaga manusia. Energi langsung yang digunakan yaitu berasal
dari bahan bakar dan listrik. Bahan bakar terbagi 2 yaitu bahan bakar minyak
(BBM) dan biomassa. BBM yang digunakan berupa solar dan bensin yang
digunakan untuk alat angkut TBS dan CPO, alat dan mesin budidaya pertanian
18
(BBM) dan biomassa. BBM yang digunakan berupa solar dan bensin yang
digunakan untuk alat angkut TBS dan CPO, alat dan mesin budidaya pertanian
serta untuk pembangkit listik tenaga diesel. Biomassa berupa serat dan
cangkang digunaken sebagai bahan bakar pada sistem boiler. Uap yang
merupakan output dati oiler digunakan untuk menggérakan turbin guna
menghasilkan listrik. Energi lisuik yang dibasilkan sistem turbin uap dan
pembangkit tenaga mesin diesel digunakan untuk Kegiatan budidaya,
pengolahan maupun sarana pendukung (Sholahuddin , 1999).
Energi tidak langsung yang digunakan yaitu pupuk dan pestisida pada
pemeliharaan tanaman serta bahan kimia yang ditambahkan pada proses
penanganan air. Energi biologis dari tenaga manusia digunakan pada semua
tahapan proses produksi serta sarana pendukung, berasal tenaga kerja yang
terkait langsung dengan proses produksi, Bagan alir proses dan masukan energi
pada produksi CPO dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gamber 5.
Hasil penelitian Sholahudin, (1999) di PIP. Nusantara VIMI (Persero)
in bahwa
perkebunan kelapa sawit (PKS) Kertajaya Banten Selatan menunjul
jumlah energi yang diperlukan untuk menghasilkan tiap kg CPO yaitu sebesar
18.6680 MJ. Dengan perincian energi langsung sebesar 7.1181 MJ dan energi
tidak langsung sebesar 11.5499 MJ. Pada penelitian tersebut audit energi
dilakuken pada kegiatan budidaya kelapa sawit dan pengolahan TBS menjadi
CPO, dengan masukan energi terbagi 2 yaitu energi tidak langsung meliputi
energi dari pupuk dan pestisida serta masukan energi langsung yang berasal
dari tenaga manusia, baban bakar minyak, biomassa dan listrik.
Analisis energi yang dilakukan di PKS Condong, Garut - Jawa Barat
yang dilakukan oleh Yose Alfira pada tahun 1999, merupakan penelitian untuk
menghitung kebutuhan energi tiap kilogram CPO yang dihasilkan dari kegiatan
pengangkutan TBS sampai kegiatan pengolahan. Variabel input energi yaitu
pertama berasal dari energi solar untuk pengangkutan TBS, pengolahan inti,
air, bengkel dan penerangan. Input energi kedua yaitu energi manusia untuk
pengolahan TBS menjadi CPO. Input energi ketiga yaitu energi biomassa
sebagai bahan bakar boiler dan keempat yaitu energi listik. Total kebutuhan
energi yang dibutuhkan yaitu 37.32063 Mi/kg CPO.
19
Alat/Mesin
‘Tahapan Proses
Masukan Energi
Pisau(alat potong) & |—>|
Persiapan bibit
alat laboratorium
}
‘Tenaga manusia,
BBM, bahan pembantu
Cangkul, Traktor
Pengolahan tanah
Tenaga manusia
pengempa
t
|| —
¥
Alat Tanam Penanaman [] Pemb. Pre ,
(Germinated seeds) peer
v
Pemb, Main nursery
v
Pers. Jahan
¥
Penanaman
¥
Pem. TBM
¥
Pem. TM
Gambar 6. Tahapan Kegiatan Budidaya Kelapa Sawit di UU Rejosari PTPN VII
1. Pembibitan
Pembibitan kelapa sawit yang dilakukan yaitu polybag nursery system
double stages, yaitu pembibitan melalui dua tahapan proses meliputi
pembibitan awal (pre nursery) dan pembibitan utama (main nursery) dengan
menggunakan polybag. Bibit awal berupa kecambah (germinated seeds)
berasal dari pusat penelitian kelapa sawit Marihat (Marihat Research Centre)
di Medan, Pelaksanaan pembibitan biasanya hampir bersamaan dengan
kegiatan persiapan lahan.
a, Pembibitan Awal (Pre Nursery)
Pembibitan awal berlangsung selama 3 bulan. ‘Tahapan pekerjaan
yeng dilakukan yaitu persiapan Jahan untuk pembibitan, persiapan tanam
bibit, pemeliharaan bibit dan pemindahan bibit ke pembibitan utama. Media
tanam yang digunakan yaitu tanah bagian atas (top soil) yang telah
dimasukan dalam baby polybag. Kecambah sebelum ditanam terlebih dulu di
sterilkan dengan fungisida yaitu Dithane M-45 dengan cara perendaman,
Pestisida yang digunakan dalam pembibitan pre mursery yaitu Ripcord yang
26
diaplikasikan melalui penyemprotan. Pupuk yang digunakan yaitu urea yang,
diaplikasikan melalui penyemprotan dengan rotasi pemupukan tiap minggu.
Sumber air untuk penyiraman berasal dari danau buatan, yang di pompa
dengan menggunakan 1 pompa yang digerakan oleh mesin diesel. Bibit yang
akan dipindahkan ke main nursery merupakan bibit yang telah diseleksi.
Seleksi yang dilakukan yaitu terhadap bibit yang mati, bibit tumbuh ganda
dan bibit abnormal.
b, Pembibitan Utama (Main Nursery)
Pembibitan utama berlangsung sekitar 9 bulan. Tahapan pekerjaan
yang dilakukan yaitu persiapan lahan, persiapan tanam, pemeliharaan dan
pemindahan bibit ke areal. Media tanam yang digunakan yaitu top soil yang
telah dicampur dengan pupuk NPK dan dimasukan dalam polybag besar.
Sistem penempatan polybag besar yang merupakan jarak tanam bibit
digunakan sistem segitiga dengan ukuran 70 cm x 70cm x 70cm dan ukuran
90 cm x 90 cm x 90 cm. Pupuk yang digunakan yaitu NPK. dan Kieserite,
sedangkan jenis pestisida yang digunakan yaitu Marshal. Sumber air untuk
penyiraman ada 2 jenis yaitu bersumber dari dari sungai dan danau buatan
yang dipompa dengan 3 buah pompa yang digerakan oleh mesin diesel.
Seleksi yang dilakukan di main nursery sama dengan seleksi yang dilakukan
di pre nursery.
2. Persiapan Lahan
Persiapan lahan yang dilakukan di UU Rejosari dilakukan untuk areal
tanaman ulang (replanting). Areal yang akan ditanam ulang merupakan areal
dimana tanaman kelapa sawitnya sudah tidak produktif Jagi. ‘Tahapen
pekerjaan pada persiapan lahan yaitu dimulai dati kegiatan mengukur/survai
areal, memancang, menumbang dan merumpuk mekanis, merencek dan
merumpuk manual, dongkel kayu, membuat Iubang besar secara mekanis,
membuat Iubang tanam secara manual dan pemberantasan gulma. Persiapan
Jahan dilakuken tanpa olah tanah, sehingga tujuan dari persiapan tahan ini
adalah upaya membersihkan lahan dan mempersiapkan lubang tanam.
27
Proses pengerjaan persiapan lahan dilakukan melalui 3 cara yaitu
secara mekanis dengan menggunakan excavator untuk membongkar tanaman
asal dan membuat lubang besar, Pengerjaan secara manual dilakukan untuk
kegiatan mengukur, memancang , membersihkan kayu-kayuan dan membuat
Iubang tanam pada Iubang besar. Pengerjaan secara kimia dilakukan untuk
membersihkan Jahan dati gulma yang menggangu, pengerjaan dilakukan
melalui wiping ilalang dan penyemprotan rumput. Lubang tanam yang dibuat
merupakan lubang besar dengan ukuran 2.5 m x 3 mx 0.5 m, serta di dalam
Iubang itu dibuat lubang kecil yang biasa disebut Iubang tanam dengan ukuran
1mx 1 mx 0.5 m, yang digunakan untuk meletakan bibit.
3, Persiapan Tanam dan Penanaman
Tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah aplikasi
tandan Kosong, penanaman legume cover crop (LCC) dan penanaman bibit.
Jarak tanam yang digunakan yaitu sistem segitiga ukuran 9 mx 9 mx 9m
dengan kerapatan 143 pohon/ha, Aplikasi tandan kosong dilakukan dengan
memasukan tandan Kosong pada lubang besar saat penanaman dengan jumlah
tandan kosong yang ditambahkan yaitu 250 kg/lubang. Penanaman dilakukan
setelah polybag bibit terlebih dulu dilepaskan, Pupuk yang ditambahkan yaitu
pupuk Rock Phospate dengan dosis 0.5 kg/lubang. Penanaman LCC
dimaksudkan untuk menekan pertumbuhan gulma, mengurangi erosi taneh,
memperbaiki infiltrasi tanah, melindungi tanah dari penyinaran matahari
langsung serta menjage kelembaban tanah.
4, Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)
Pemeliharaan TBM merupakan upaya perawatan tanaman dari sejak
tanam di areal sampai tanaman berumur kurang lebih 3 tahun, Tahapan
pekerjaan yang dilakukan yaitu pemeliharaan jalan, penyulaman, wiping
ilalang, selective weeding, bokoran, pemupukan, tunas pasir, kastrasi, sensus
hama dan penyakit, pemberantasan hama dan penyakit sera pembuatan
tempat pengumpulan hasil (TPH). Penyulaman dilakukan untuk mengganti
28
tanaman yang mati, rusak atau tumbuh abnormal. Penyulaman dapat
dilakukan sampai tanaman berumur 5 tahun.
Wiping ilalang merupakan upaya untuk memberantas ilalang dengan
cara dilap menggunakan larutan herbisida yaitu Round Up. Selective weeding
merupakan upaya untuk membersihkan areal dari gulma selain rumput,
misalnya pohon kecil atau tanaman sawit yang tumbuh akibat dari biji yang
Jatuh. Bokoran merupakan upaya untuk membersihkan daerah sekitar pokok
tanaman. Tunas pasir merupakan upaya sanitasi dan mengurangi penghalang
pembesaran buah, ini dilakukan dengan memotong pelepah.
Kastrasi merupakan upaya untuk merangsang pertumbuhan vegetatif,
mendapatkan buah dengan berat dan jumlah tandan yang seragam serta
sebagai upaya sanitasi. Kastrasi dilakukan dengan memotong bunga jantan
sampai umur 28 bulan dan bunga betina sampai umur 30 bulan. Jenis hama
dan penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit yaitu ulat api,
kumbang dan tikus, Upaya pemberantasan dilakukan secara kimia dengan
pemberian pestisida. Pestisida yang digunakan yaitu Ripcord, Phyton dan
Tikumin, Pada saat peralihan dari TBM ke TM, maka dibuat TPH dengan
ukuran 2 mx 2m.
5. Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)
Kegiatan pemeliharaan TM dilakukan selama umur tanaman masih
produktif. Pada prinsipnya pekerjaan yang dilakukan pada pemeliharaan TM
sama dengan pada pemeliharaan TBM, yang membedakannya yaitu rotasi
dari tiap pekerjaan.
B. Pemanenan
Varietas Tenera dapat dipanen pada umur sekitar 32 bulan, Buah
menjadi masak 5 bulan sampai 6 bulan setelah penyerbukan. Kriteria buah
matang panen ditentukan saat kendungan minyak maksimal dengan
kandungan asam lemak bebas minimal. Kriteria matang panen.
pada Tabel 11. Kriteria matang panen secara fisik yang sering dijadikan acuan
oleh mandor panen dan pemanen yaitu minimal 10 brondolan jatuh ke tanah
29
pada tanaman muda dan minimal 15 brondolan pada tanaman tua. Tanaman
kelapa sawit mempunyai umur produktif selama 25 tahun. Data produksi TBS
di UU Rejosari dapat dilihat pada Lampiran 2.
Tabel 11 . Standar Tingkat Kematangan Buah
Fraksi buah Persyaratan Sifat fraksi, Jumlah brodoian
Fraksi_00 0.0 Sangat mentah | Tidak ada
Fraksi_0 Maks. 3.0% | Mentah 1.0=12.5 % buah luar
Fraksi_1 Kurang matang_[12.5-25.0 % buah luar
Fraksi_ 2) 85% Matang 25.0 - 50.0 % buah Ivar
Fraksi_ 3 Matang 50.0- 75.0 % buah luar
Fraksi_ 4 Maks. 10.0% | Lewat matang | 75.0— 100.0% buah luar
Fraksi_5 Maks. 2% | Terlalumatang | Buah dalam membrondol
Brondolan 9.5%
“Tandan kosong 0.0%
Panjang tankai TBS | Maks 2.5 cm
Sumber : Anonimous (1993)
Sistem panen yang dilakukan yaitu ancak giring yang berarti setiap
pemanen berpindah areal panen sesuai petunjuk mandor. Rotasi panen yang
dilakukan yaitu 5/7 untuk keadaan produksi buah normal. Rotasi 5/7 berarti
dalam satu Iuas areal tertentu dibagi menjadi 5 hari panen dengan rotasi ulang
7 hati, Peralatan utama yang digunakan yaitu kampak dan dodos yaitu
sejenis linggis bermata lebar dengan gagang panjang yang digunakan untuk
ketinggian tanaman sekitar 2 m sampai 5 m. Untuk ketinggian lebih dari 5m
digunakan egrek berupa sabit bergagang bambu panjang. Kegiatan
pemanenan meliputi kegiatan memanen tandan buah, memungut tandan dan
brondolan serta mengumpulkannya di TPH.
. Pengangkutan Buah
Tandan dan brondolan yang jatuh diangkut dan dikumpulkan di TPH.
Buah yang terkumpul harus segera diangkut pada hari itu juga, untuk
menghindari peningkatan kadar asam lemak bebas. Pemindehan dari TPH ke
truk pengangkut TBS dilakukan oleh 2 orang dengan alat bantu cungkil yaitu
berupa batang besi yang dibengkokan pada ujungnya, dengan ujung batang
runeing dan tajam. Truk yang digunakan untuk mengangkut TBS ke pabrik
terbagi dua yaitu truk milik PTPN VII dan truk sewaan dengan sistem
30
kontrak yang didasarkan pada daya angkut truk (tonase) dan jarak dari kebun
ke pabrik. Kapasitas rata-rata tiap truk sekitar 6 ton TBS/sekali angkut. Tiap
truk dalam satu hari melakukan 2 kali - 3 kali pengangkutan tergantung
kondisi truk, jarak kebun ke pabrik dan jumlah TBS yang dipanen.
D, Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi CPO
Pengolahan kelapa sawit menjadi CPO di UU Rejosari dapat dilihat
pada Gambar 7 dan Lampiran 2. Sedangkan aliran bahan pada peralatan yang
digunakan dapat dilihat pada Gambar 8, Pabrik pengolahan kelapa sawit UU
Rejosari, mulai beroperasi dari tahun 1990, dengan kapasitas olah terpasang
yaitu 25 ton TBS/jam dengan jam operasi yaitu 20 jam/hari, sehingga
kapasitas olah terpasang_tiap hari yaitu 500 ton TBS. Data produksi CPO di
UU Rejosari sejak mulai beroperasi dapat dilihat pada Lampiran 4, dengan
rata-rata rendemen TBS menjadi CPO yaitu 20.89 %. Sedangkan data waktu
pengolahan riil dapat dilihat pada Lampiran 5, Pengolahan TBS menjadi CPO
menghasilkan hasil sampingan berupa tandan kosong yang digunakan untuk
pupuk, serat dan cangkang untuk bahan bakar boiler serta biji sawit untuk
menghasilkan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO).
‘TBS dari kebun.
——
Penerimaan buah
¥
Perebusan
+
Penebahan
v
Pelumatan dan pengempaa
—— 1;
Pengolahan biji Pemurnian minyak
Gambar 7, Bagan Alir Pengolahan Kelapa Sawit di UU Rejosari
31
ALAT TIMBANG
¥
LOADING RAMP
w
STERILIZER
Ye
THRESSER
¥
DIGESTER
¥
SCREW PRESS
‘SAND TRAP TANK cac
¥ ¥
VIBRATING SCREEN DEPERICARPER
¥.
CRUDE O1L TANK POLISHING DRUM
¥ ¥
— csr ‘NUT SILO
I ¥
¥ + NUT GRADING
OU TANK ‘SLUDGE TANK ¥
= ¥ NUT CRACKER
OIL PURIFIER ‘BRUSH STRAINER ¥
¥ ¥ VIBRATING GRADE
VACUUM DRYER DECANTER v
¥. *. SEPARATING COLOUM
STORAGE TANK RESIDU TANK
¥ ¥
FAT FIT KERNEL SILO
¥
KERNEL RAGING BIN
Gambar 8. Aliran Bahan Pada Alat Pengoleh Kelapa Sawit Menjadi CPO
1. Penerimaan Buah
Tahapan proses yang terjadi pada stasiun penerimaan buah ini adalah
penimbangan buah, sortasi buah, penimbunan buah sementara di loading
ramp dan pengisian buah ke lori rebusan. TBS yang masuk ke pabrik
ditimbang untuk mengetahui berat total TBS sebagai data produksi panen,
data untuk memperkirakan rendemen CPO serta data untuk penentuan biaya
32
angkut untuk TBS yang diangkut tuk sewa. TBS yang telah ditimbang
kemudian di turunkan di loading ramp. ‘TBS ini diperiksa secara visual yang
dimaksudkan untuk melihat fraksi buah yang akan diolah. TBS yang berada
4i loading ramp kemudian dicurahkan ke lori rebusan yang bergerak pada rel.
2. Perebusan
Tujuan proses perebusan yaitu agar buah mudah dilepas dari
tandannya, inaktivasi enzim lipase, melunakan daging buah, melonggarkan
inti dari cangkang dan menambah kelembaban daging buah schingga minyak
muda dikeluarkan. Sistem perebusan yang dipakai yaitu sistem perebusan
tiga puncak atau sriple peak sterilization.
Tahapan proses dalam sistem perebusan ini dimulai dari deaerasi
(pembuangan udara), pengisian steam (puncak I) sampai tekanan 1.4 kg/om?,
pembuangan sfeam sampai tekanan 0.4 kg/cm’, pengisian steam (puncak II)
sampai tekanan 2.0 kg/cm’, pembuangan steam sampai tekanan 0.6 kg/cm?
dan perebusan (puncak III) dengan tekanan 2.8 kg/em? — 3 kg/em?,
pembuangan air kondensat (setelah perebusan selesai) dan terakhir adalah
pembuangen uap (blow off). Sumber steam berasal dari unit boiler yang
didistribusikan ke unit perebusan melalui back pressure vessel (BPV). Buah
yang sudah direbus beserta lorinya, kemudian diangkat dengan hoisting crane
untuk dicurahkan ke auto feeder. Tahapan pengangkutan dengan hoisting
crane dimulai dari mengangkat lori, mencurahkan buah dan menurunkan lori.
3. Penebahan
Proses ini bertujuan untuk memisahkan buah dari tandannya. Alat
yang digunakan yaitu auto feeder dan thresser. Buah yang dicurahkan oleh
hoisting crane ditampung dalam auto feeder dengan kemiringan lantai curah
yang dapat diatur sebagai mekanisme pengaturan buah masuk ke thresser.
Prinsip penebahan yaitu dengan membanting bush dalam drum yang berputar.
Bagian dalam drum berbentuk kisi, sehingga buah yang sudah terpipil akan
akan lolos ke bawah lalu masuk ke under thresser conveyor, sedangkan
tandan kosong terdorong keluar dan masuk ke empty bunch conveyor. Pada
proses penebahan ini Kehilangan minyek terjadi karena buah terbanting
sehingga minyak sebagian akan keluar dan terserap oleh tandan Kosong,
4, Pelumatan dan Pengempaan
Alat utama pada stasiun ini adalah digester dan serew press. Proses
yang terjadi pada digester yaitu melumatkan buah dengan bantuan panas dan
pisau perajang yang sekaligus berfingsi sebagai pengaduk. Bush yang telah
dilumatkan, masuk ke screw press untuk dikeluarkan minyaknya melalui
pengempaan. Screw press terdiri dari 2 buah silinder yang berlubang dan
didalamnya terdapat dua ulir (screw) yang berputar berlawanan ara. Minyak
hasil pengempaan akan keluar melaui lubang silinder kemudian masuk ke
sandtrap tank, sedangkan ampas (cake) yang berupa serat dan biji akan keluar
dari bagian depan screw press lalu masuk ke cake breaker conveyor (CBC).
5, Pemurnian Minyak
Minyak dari screw press ditampung dalam sandtrap tank untuk
memisahkan pasir yang terbawa minyak mentah, Mekanisme pemisahan
yaitu pengendapan, sehingga partikel padat yang mempunyai berat jenis lebih
besar akan mengendap. Dari sandirap tank minyak masuk ke saringan
bergetar (vibrating screen). Vibrating screen digunakan untuk memisahkan
padatan dengan penyaringan. Vibrating sereen terdiri dari 2 tingkatan
penyaringan yaitu bagian atas berukuren 20 mesh den bagian bawah
berukuran 40 mesh. Minyak yang sudah disaring kemudian masuk ke crude
oil tank (COT) , pada tangki ini kotoran dipisahkan melalui pengendapan,
Dati COT, minyak masuk ke continous setling tank (CST), untuk pengutipan
minyak. CST dilengkapi dengan skimmer yaitu semacam corong yang
ketinggiannya bisa diatur untuk mengutip minyak. Mekanisme pengutipan
didasarkan pada perbedaan berat jenis antara minyak dengan air dan kotoran,
dimana minyak dengan berat jenis kecil akan berada pada permukaan atas.
Minyak yang terkutip akan masuk ke oil tank dan dipisahkan lagi dari kotoran
melalui pengendapan, sedangkan bagian yang tidak terkutip berupa sludge
akan masuk ke s/udge tank, Minyak dari oi! tank masuk ke oil purifier yang
berfungsi untuk memurnikan minyak dari kotoran-kotoran. Mekanisme
34
pemurian minyak didasarkan pada gaya sentrifugal, di dalam alat ini minyak
diputar. Karena gaya sentrifugal, minyak yang mempunyai berat jenis ringan
akan akan bergerak ke tengah (poros) lalu keluar dan dialirkan ke vacuum
dryer. artikel padat dan air akan terdorong ke dinding dan keluar melalui
nosel yang ada di dinding tersebut. Prinsip pengeringan di vacuum dryer
didasarkan pada perbedaan suhu penguapn antara air dengan minyak, dimana
air mempunyai suhu penguapan yang lebih rendah dari pada minyak. Minyak
disemprotkan dengan nosel sehingga berbentuk kabut dan proses pengeringan
akan berlangsung lebih cepat. Minyak yang sudah dikeringkan akan turun dan
ditampung ke tangki timbun (storage tank). Dari CST bagian yang tidak
terkutip akan masuk ke s/udge tank untuk diendapkan dan kemudian masuk ke
brush strainer untuk membersihkan serabut yang terbawa sludge. Dalam
brush strainer terdapat brush (sikat) yang berputer, sehingga serabut akan
tertahan dan menempel di sikat. Dari brush strainer kemudien masuk ke
decanter, dengan prinsip pemisahan yang sama dengan oil purifier. Dari
decanter bagian yang terkutip (fraksi ringan) akan masuk ke residu tank lalu
diendapkan dan akan dikembalikan ke CST, sedangkan fraksi berat dari resid
tank akan masuk ke fat fit untuk dikutip kembali. Fat fit merupakan tempat
untuk menampung fraksi berat dari residu tank, water drab separator, air
kondensat, air cucian dari dari peralatan di stasiun pemurnian dan minyak
yang bocor atau yang tertumpah sehingga minyak dapat dikutip kembali. Far
‘fit terdiri dari bak yang tersambung, dengan tiap bak dilengkapi dengan
skimer. Fat fit ini terbagi dua yaitu fat fit baja, yang terdiri dari bak-bak
terbuat dari baja dan fat fit tanah yang merupaken kolam-kolam pada
permukaan tanah. Pengutipan minyak dimulai dari fa fit baja kemudian ke fat
Jit tanah,
6. Pengolahan Biji
Ampas screw press yang masih berbentuk gumpalan yang terditi dati
serat dan biji, akan masuk ke cake breaker conveyor (CBC) untuk pemecahan
gumpalan tersebut. Dari CBC ampas masuk ke depericarper untuk dipisahkan
antara serat dan biji. Sistem pemisahan dengan menggunakan hisapan angin
dari blower. Fraksi ringan (serat) akan tertarik ke atas lalu massuk ke fibre
35
conveyor untuk diangkut ke boiler. Fraksi berat yaitu biji (nu) akan jatuh dan
masuk polishing drum, untuk memisahkan serat yang masih menempel di biji.
Mekanisme kerja polishing drum yaitu biji yang masuk ke dalam drum yang
berputar dan bergeseken dengan dinding drum yang bersekat, Akibat putaran
dan gesekan tersebut serat yang masih menempel pada biji akan terlepas. Biji
Kemudian akan masuk ke mut conveyor untuk dikeringkan di nut silo.
Pengeringan di mu sifo dimaksudkan untuk melonggarkan inti dari cangkang,
sehingga akan mempermudah pemecahan biji dalam nut cracker. Nut silo
terbagi ke dalam 3 ruangan yaitu bagian atas, tengah dan bawah, lama
pengeringan yaitu sekitar 20 jam, Sumber panas untuk pengeringan berasal
dari heater yang berisi steam, sedangkan udara segar berasal dari udara
lingkungan yang ditarik menggunakan blower. Biji yang teleh dikeringkan
akan masuk ke mut grading screen yaitu alat sortasi biji berdasarkan
Giameternya, Ukuran lubang disesuaikan dengan diameter yang akan disortasi
yang terdini dari 3 fraksi yaitu fiaksi kecil ukuran 8 mm — 14 mm, fiaksi
sedang ukuran 15 mm — 17 mm dan fraksi besar ukuran lebih dari 17 mm
Biji tersebut akan masuk berdasarkan fraksinya ke nut cracker, untuk
dipecahkan melalui mekanisme bantingan, dan biji akan terpecah menjadi inti
yn masuk ke
dan cangkang. Inti dan cangkang deri nut cracker kemuk
separating coloum untuk dipisabkan, Prinsip pemisahan yaitu berdasarkan
hisapan angin. Akibat perbedaan berat maka cangkang (shell) akan naik ke
atas dan masuk ke shell conveyor untuk diangkut ke boiler. Inti (kernel)
akan turun dan masuk kernel conveyor untuk dikeringkan di kernel silo.
Proses Pengeringan di kernel silo sama dengan pengeringan di mut sifo, hanya
bedanya yaitu waktu pengeringan di kernel silo sekitar 11 jam. Inti yang
telah dikeringkan kemudian akan masuk ke kernel bagging bin untuk
penyimpanan dan selanjutnya diangkut untuk di olah menjadi minyak inti
sawit/ paln kernel oil (PKO).
36
E. Sarana Pendukung
1. Penyediaan air
Pabrik kelapa sawit membutubkan air bersih untuk pengolahan dan
umpan boiler. Air yang digunakan harus memenuhi standar sebelum
digunakan untuk proses, misalnya dari kandungan bahan-bahan kimianya,
bahan padatan terlarut dan sebagainya, sehingga sebelum digunakan terlebih
dulu air tersebut harus dijernihkan. Penanganan air ini terbagi dua yaitu yaitu
external treatment dan internal treatment.
a. External Treatment
Air awal (raw water) berasal dari sungai Titirante sejauh + 1 Km
yang diambil dengan pemompaan Ialu ditampung dalam suatu bak
penampung dan dipompa ke /ower tank pada bagian air mentah . Tower tank
ini mempunyai 3 sekat penampungan yaitu untuk air mentah (raw water), air
untuk internal treatment dan sir untuk kebutuhan domestik, Selanjutnya air
masuk ke sand filter untuk menyaring pasir kemudian masuk ke water basin
(bak penampung). Dati water basin air dialiskan ke clarifier tank untuk untuk
mengendapkan Kotoran, kemudian dialirkan kembali ke cower sank pada
bagian incernal treatment, Bahan kimia yang ditambahkan dalam external
treatment ini yaitu tawas dan Floc 65.
b. Internal Treatment
Internal treatment merupakan perlakuan lenjutan terhadap air yang
akan digunakan untuk umpan boiler. Air dari tower tank akan masuk ke
penukar kation untuk menarik ion positip kemudian dialirkan ke degasifier
untuk membebaskan gas - gas tertentu yang terbawa air. Dari degasifier air
masuk ke penukar anion untuk menarik ion negatip, setelah itu masuk ke
tangki heater untuk untuk memanaskan air, selanjutnya masuk ke deaerator
untuk menarik oksigen yang terlarut dalam air. Bahan kimia yang
ditambahken dalam internal treatment ini adalah WITCO BWT 2200,
WITCO BWT 2041 dan WITCO BWT 2430.
37
2. Penyediaan Energi
Penyediaan energi merupakan sarana pendukung proses produksi yang
berperan untuk memasok kebutuhan energi untuk pengolahan, sarana
pendukung maupun kebutuhan domestik (kantor, perumahan dan lain-lain).
Dalam hal ini penyediaan energi_yang akan diuraikan yaitu penyediaan energi
untuk pengolahan dan sarana pendukung produksi. Energi yang berasal dari
sarana pendukung penyediaan enrgi ini berupa listrik dan uap. Peralatan
utama yang ada di sarana penyediaan energi ini adalah boiler, wrbin uap, back
pressure vessel (BPV) dan mesin pembangkit tenaga diesel.
a. Boiler
Boiler merupakan instalasi untuk mengubah air menjadi wap panas
bertekanan tinggi dengan bantuan dari pemanasan yang diperoleh dari hasil
pembakaran, Boiler yang ada di UU Rejosari berjumlah 2 unit yaitu 1 unit
dipakai dan 1 unit sebagai cadangan, dengan kapasitas masing-masing sebesar
18 m? uap/jam dengan tekanan 19 kg/em? — 20 kg/em?. “Bahan bakar dari
boiler ini adalah cangkang dan serat yang merupakan limbah padat dari
pengolahan. Rendemen serat dan cangkang yang dihasilkan dari tiap kg TBS
yang diolah yaitu berturut-turut sebesar 12.50 % dan 6.45 % dengan kadar air
untuk serat yaitu 41.22 % dan cangkang sebesar 10.85 %.
Bagian-bagian dari boiler yaitu ruang bakar, upper drum, lower drum,
pipa saturated, pipa superheated, rvang masuk bahan bakar, pembuangan abu
(dust collector), cerobong, blower tekan, blower hisap dan alat-alat kontrol.
Proses pembakaran dimulai ketika serat dan cangkang mulai masuk ke five!
feeding melalui fibre conveyor dan shell conveyor, dalam fuel feeding ini
serat dan cangkang dicampur untuk menjadi bahan baker boiler. Selanjutnya
udara luar ditarik dengan blower tekan dan proses pembakaran dimulai. Air
‘umpan dari internal treatment dipompa, kenmudian masuk ke upper drum, pipa
saturated dan lower drum. Air tersebut mendidih dan terbentuk vap
saturated. Untuk mengubah menjadi uap superheated maka uap saturated
dari upper drum dialirkan ke pipa superheated yang diletakan di bagian
belakang ruang pembakaran, Kerak sisa pembakaran yang cukup berat akan
jatuh ke bagian bawah melalui kisi pembakaran. Gas dan abu sisa
38
pembakaran keluar melalui cerobong yang dihisap dengan olch blower hisap,
fiaksi berat (abu) akan jatuh di dust collector yaitu pengumpul abu berupa bak
berisi air.
b. Turbin Uap
Turbin wap merupakan instalasi pengubah uap menjadi gerak mekanis
berupa putaran lalu diubah menjadi bentuk energi listrik. Turbin uap yang
digunakan berjumlah 2 unit dengan daya listrik output terpasang yaitu 950
kW. Uap dari boiler yang telah digunakan untuk memutar turbin kemudian
di tampung dalam BPV yaitu berupa bejana/tangki. Dari BPV kemudian uap
didistribusikan ke instalesi pengolahan.
c. Generator Diesel
Generator diesel merupakan peralatan untuk mendukung penyedian
energi listrik dari turbin uap, terutama saat-saat awal mulai pengolahan
dimana pasokan energi listrik dari boiler belum optimal, saat pemakaian
energi listrik meningkat atau kualitas uap dari Boiler kurang sehingga listrik
dari turbin uaap juga kurang. Generator diesel yang digunakan berjumlah 4
unit dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 325 kW.
3. Penanganan Limbah
a. Limbah Padat
Limbah padat yang dihasilkan dari pabrik pengolah kelapa sawit
menjadi TBS di UU Rejosari terbagi 4 yaitu tandan kosong, serat, cangkang
dan padatan (solid). Rendemen tandan kosong yang dihasilkan dari tiap kg
TBS yang diolah adalah sebesar 25.34 %. Tandan kosong yang keluar dari
empyy bunch conveyor kemudian dikumpulkan dengan steer loader untuk
dipindahkan ke truk pengangkut dan dibawa ke kebun untuk dijadikan pupuk.
Serat yang keluar dari depericarper digunakan untuk bahan bakar boiler.
Cangkang yang berasal dari separating coloum juga digunakan untuk bahan
bakar boiler sedangkan padatan (solid) yang keluar dari decanter tidak
dimanfaatkan, hanya dibuang ke sekitar lingkungan pabrik karena_jumlahnya
tidak terlalu banyak.
a9
b. Limbah Cair
Limbah cair yang masuk ke kolam limbah merupakan bagian yang
tidak terkutip di far fit tanah. Far fit tanah ini sebenamya berfangsi juga
sebagai cooling pond (kolam pendingin), schingga limbah cair yang akan
masuk ke kolam limbah suhunya sudah turun dari sekitar 80 ° C menjadi
sekitar 45°C, Dati cooling pond kemudian limbah masuk ke kolam anaerob
untuk penguraian limbah oleh bakteri anaerobik melalui proses hidrolisa,
pengasaman, pembentukan asam asetat dan gas methan. Dari kolam anaerob
limbah cair lalu masuk ke kolam aerobik untuk penguraian limbah cair
dengan bakteri aerobik. Limbah cair tersebut kemudian dipompa ke land
aplication (areal aplikasi limbah cair) untuk digunakan sebagai pupuk.
4. Laboratorium
Laboratorium berfungsi sebagai tempat pengawasan mutu dari hesil
produksi pengolahan. Analisis mutu hasil produksi meliputi analisis kadar air,
kadar asam lemak bebas, kadar kotoran dan kadar minyak hilang. Analisis
juga dilakukan terhadap air umpan boiler meliputi analisis kesadahan, pH,
silika, total padatan terlarut dan alkalinitas, Analisa limbah cair dilakukan
oleh PT. Sucofindo meliputi suhu, derajat keasaman (pH), biological oxygen
demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), suspended solid (SS) dan
toral solid (TS). Salah satu analisis penting yang dilakukan di laboratorium
yainu penentuan neraca bahan (material balance). Neraca bahan merupakan
penetapan komponen hasil pada setiap tahapan proses dari TBS yang diolah.
Neraca bahan penting untuk melihat karakteristik dari TBS. Peralatan yang
digunakan di laboratorium yaitu drying oven, timbangan manual dan
timbangan digital serta peralatan kimia seperti cawan, labu, gelas ukur dan
lain-lain.
E. Bengkel dan Bagian Teknik
Upaya perawatanv/imaintenance merupaken upaya penting untuk
mendukung jalannya proses produksi. Upaya ini dilakukan melalui bagian
teknik yang ditunjang dengan bagian bengkel. Bagian teknik di UU Rejosari
40
terbagi 2 yaitu bagian teknik reparasi dan tenik listrik dan gir. Teknik
eparasi bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan dan_perawatan
peralatan produksi, penggantian spare part, pengecekan dan inventarisasi
peralatan di pabrik. Teknik listrik dan air bertanggung jawab untuk perawatan
dan perbaikan instalasi listrik serta instalasi air. Sedangkan perbaikan dan
perawatan alat angkut seperti truk, mobil dinas, traktor dan steer loader
dilakukan oleh bagian traksi.
41
IV. METODOLOGI PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di unit PIP. Nusantara VI (Persero) Unit
Usaha Rejosari - Lampung Selatan, Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada
bulan Agustus 2001 sampai Oktober 2001.
B. Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan dalam petelitian ini adalah TBS yang
kemudian diolah menjadi CPO, bahan bakar solar, serat (ftbre,) cangkang
(shell), biji sawit (nut) dan inti sawit (kernel).
Peralatan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari peralatan
utama yang merupakan alat dan mesin yang digunakan di UU Rejosari PTPN
VII (Persero), serta alat ukur yang terpasang pada kamar mesin (power
house), alat ukur yang terpasang pada alat-alat produksi (termometer,
manometer, flow meter), stopwatch, drying oven, timbangan, AVO meter,
bomb calorimeter, termometer dan kapas.
C. Pendekatan Masalah dan Batasan Sistem
Dalam penelitian ini sistem yang diamati yaitu proses produksi CPO di
PTP. Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari - Lampung Selatan,
meliputi Kegiatan budidaya, panen, pengangkutan buah dan pengolahan
kelapa sawit menjadi CPO serta sarana pendukung proses produksi meliputi
penyediaan energi, penyediaan air, penanganan Jimbah, laboratorium dan
bengkel serta bagian teknik, Sistem produksi yang diaudit dapat dilihat pada
Gambar 9. Sedangkan bagan alir proses dan masuken energi di UU Rejosari
PTPN VII (Persero) dapat dilihat pada Gambar 10. Input energi primer yang
pertama yaitu energi langsung yang berasal dari bahan bakar minyak (solar)
dan biomassa. Energi yang beresal dari sistem boiler yaitu uap maupun
listrik dari turbin uap dan generator diesel tidak dianggap sebagai input
energi, yang dipethitungkan hanya bahan bakar dari kedua sistem itu (boiler
dan diesel). Tetapi energi listrik untuk setiap tahapan produksi tetap dihitung
Kecambah_}-| Pembukaan dan Persiapan lahan
¥
Pembibitan
Mesin dan ¥
Peralatan Peranaman
Budidaya
» Y
Pemeliharaan
Pemanenan
¥.
Pengangkutan Buah
aoa =k
Penerimaan Bush
¥.
Truk Perebusan
Mesin dan
Peralatan i=
Pengolatvan Boiler
Penanganan
Limbah
Bengkel
Pemurnian Minyak
Pengeringan dan Pemecahan Bij
¥
Laboratorium
Penyediaan Air
Penerangan
Keterangan :
Batasan Sistem Input Energi Langsung
Aliran Proses Input Energi Tidak Langsung
Input Listrik Input Tenaga Manusia
Input Uap BPV : Back Pressure Vessel
Gambar 9. Batasan Sistem Yang Akan Diaudit
43
Alat/Mesin Tahapan Proses Masukan Energi
Sprayer, Pompa —_" Pembibitan Manusia, solar, pupuk, pest,
¥
Excavator | >__Persiapan tahan — [X—] —Manusia, solar, pestsida
¥
Alat tanam |\—>) Penanaman i<— ‘Manusia, pupuk
¥
Sprayer |—>|_Pem, Tanaman Je —[ stansia, popu pestisida
¥
Egrek, dodos, kapak = |-——> Pemanenan i<— “Manusia
¥
‘Truk |—>_Pengangkutan buah = [{__ Penerimaan buah fe —f Manus, lsrik
v
Sterilizer Perebusan_ Manusia, vap
Hoisting crane, Auto feeder, Y
oe a Penebahan <<] Manusia,listrik, wap
v
Digester , Screw press. |}—>| Pengempaan <—| —— Manusia, lstik, uap
ibang sreen, sand tap
tank, sandy eyfone, CST,COT,
sludge tank, vacuum diver,” |p| Pemurnian lk—{ anus, sri, wap
‘oil purer, decanter, resid
tank
(CRC, depertcarper,nut
polishing cron, nile
radi, nu cracker, Pengolahan bi —[_ Manus isi, uap
wating gre separaing
Celouns rel fo, kere
‘in
|
Pompa raw seater, internal
‘daw external treatment
ea ‘Manusi, list, wap, baba
Penyedisan air Kimia
‘Steer loader, tk, pompa
and aplication
Penanganan limbah_f¢-——-| — Manusia, istrik, solar
—
Boiler, cabin vap, BPV, - 7 anus sik,
inn dsl |—>[__Penyesiaanenersi fX—] nn
||
|-—>|
Vacuum drying, tinbangan,
na a
ack Ss ;
Gambar 10. Bagan Alir Proses dan Masukan Energi Pada Produksi CPO di UU
Rejosari PTPN VII
44
sebagai input energi_pada tahapan produksi tersebut. Input energi primer yang
kedua yaitu energi tidak langsung yang berasal dari pupuk. Input cnergi tidak
langsung dari pestisida dan bahan kimia pembantu hanya dihitung sebagai
jumlah konsumsi bahan tiap kilogram CPO yang dihasilkan. Input energi
primer yang ketiga yaitu energi biologis yang berasal dari tenaga manusia.
Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kesulitan untuk menerapkan
audit energi terhadap sistem yang diteliti. Untuk itu diperlukan batasan-
batasan sebagai berikut :
1. Proses produksi untuk menghasilkan CPO dimulai dari kegiatan budidaya
sampai dengan pengolahan TBS menjadi CPO serta produk sampingannya
(bi
dianggap satu kesatuan sistem produksi.
dan inti) dengan ditunjang oleh sarana pendukungnya dan hal ini
2. Pada saat pengamatan rinci tiap tahapan proses, tahapan proses produksi
CPO yang sedang diamati dienggap merupakan tahapan proses produksi
yang dapat diputus dari tahapan sebelum dan sesudahnya.
3. Pengamatan terhadap proses produksi CPO dilakukan secara berurutan
mengikuti proses yang terjadi.
4, Semua kegiatan dan jalannya proses produksi CPO dianggap tetap setiap
tahunnya dan dalam keadaan normal.
5.Dalam proses produksi CPO, semua embodied energy dari mesin dan
peralatan pabrik serta peralatan bengkel tidak diperhitungkan karena
krurangya data pendukung.
6. Input energi tidak langsung dari pestisida dan bahan kimia pembantu tidak
diperhitungkan dalam perhitungan kebutuhan energi produksi tiap kg CPO
karena kurangnya data pendukung, tetapi tetap diaudit dan disajikan
sebagai data pelengkap dalam bentuk satuan unit bahan (bukan satuan unit
energi).
7.Pada kegiatan budidaya, energi langsung dari sinar matahari tidak
diperhitungkan.
8.Pada kegiatan perbaikan dan perawatan peralatan dan mesin yang
digunakan, konsumsi energi dari bahan pelumas tidak diperhitungkan.
45
9. Dalam audit ini, jumlah TBS (kg/ha) yang dijadikan sebagai variabel rata-
rata produksi yang digunakan untuk menghitung input energi pada kegiatan
budidaya merupakan produksi TBS selama umur produktif yaitu 25 tahun
untuk Iuasan satu hektar.
10. Semua input energi untuk kegiatan pengolahan dan sarana pendukung,
didasarkan pada produksi CPO tiap hari. Dalam audit ini jumlah CPO (kg
CPOMhari) yang dijedikan variabel rata-rata produksi merupakan jumlah
produksi CPO selama satu hari olah.
11. Input energi primer dihitung dari masukan energi pupuk, manusia, solar dan
biomassa. Masukan energi listvik yang merupaken input energi sekunder
yang berasal dati solar dan biomassa hanya dihitung pada tiap tahapan
produksi yang mengkonsumsinya.
12, Masukan energi listrik hanya dihitung untuk kegiatan yang langsung
berhubungan dengan proses produksi. Penggunaan listrik untuk peralatan
dan penerangan kantor serta kebutuhan listrik untuk perumahan karyawan
tidak dihitung
13. Masukan energi biologis tenaga manusia hanya dihitung yang langsung
berhubungan dengan proses produksi. Untuk pegawai administrasi, mandor
dan seterusnya tidak dihitung,
D. Metode Audit
Metode audit yang dipakai dalam penelitian ini adalah audit energi
awal (preliminary energy audit) yang dilanjutkan ke tahap audit energi terinei
(detailed energy audit). Tahapan audit energi rinci yang dilakukan adalah
pemilihan bagian-bagian yang akan diaudit rinci, persiapan kelengkapan kerja,
pemeriksaan data lapangan, evaluasi data yang dikumpulkan dan
mengidentifikasi peluang konservasi energi.
Metode analisis energi yeng akan digunakan yaitu metode analisis
proses. Dimana setiap tahapan proses atau kerja dianalisis untuk menentuken
masukan energi dan analisis ini merupakan suatu identifikasi’ terhadap
jaringan kerja dan proses yang harus diikuti untuk memperoleh produk akhit.
46
Pelaksanaan audit energi dimulai dengan menentukan batasan sistem
yang akan diaudit, dilanjutkan dengan menghitung semua input yang
termasuk ke dalam sistem, kemudian mengidentifikasi output yang dihasilkan
dalam satuan yang sama yaitu, sehingga akan diperoleh jumlah energi
produksi dalam satuan MJ/kg CPO. Langkah selanjutnya yaitu menentukan
effisiensi dari tip tahapan proses produksi sekaligus mencari energi yang
terbuang schingga upaya penghematan dapat dilakukan. Tahapan penelitian
yang dilakukan disajikan pada bagan alir dalam Gambar 11.
Penentuan batasan sistem
v
Pre Audit
¥
Audit Rinei
_______]
Perbandingan dengan lokasi lain
pada komoditi yang sama
©
Rekomendasi
Gambar 11. Bagan Alir Penelitian
Perhitungan terhadap masukan energi yang digunakan dilakukan pada
setiap tahap yeng telah ditentukan, dimana setiap masukan baik berupa energi
langsung maupun energi tidak langsung dikonversikan ke dalam satuan energi
yang sama yaitu Mega Joule (MJ). Hasil penelitian yang diperoleh kemudian
dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan pada lokasi
berbeda, untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
penggunaan energi pada proses produksi CPO.
47
E. Parameter Yang Diukur
Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah :
1. Kebutuhan Energi Manusia
Variabel yang digunakan meliputi hari kerja orang (HKO), jumlah jam
kerja, nilai unit tenaga manusia, jumlah produksi TBS dan CPO.
2. Kebutuhan Energi Listrik
Variabel yang digunakan meliputi jumlah dan jenis alat, jam jalan alat,
daya, tegangan dan arus listrik yang terpasang dan terukur, faktor daya
liswik, fasa arus dan jumiah produksi CPO.
3. Kebutuhan Energi Bahan Bakar Minyak (Solar)
Variabel yang digunakan meliputi konsumsi solar, nilai kalor solar, jumlah
produksi TBS dan CPO.
4, Kebutuhan Energi Biomasa
Variabel yang digunakan meliputi jumlah cangkang dan serat yang
dihasilkan dan dikonsumsi, nilai kalor cangkang dan serat, jam jalan boiler,
subu air umpan, subu uap, tekanan vap, laju uap, tekanan BPV, suhu BPV
dan jumlah produksi CPO.
5. Energi Pupuk
Variabel yang digunakan pada penelitian i
kalor jenis pupuk dan produksi TBS.
6. Kebutuhan Pestisida
Variabel yang digunaken pada penelitian ini adalah konsumsi pestisida dan
produksi TBS.
7. Kebutuhan Bahan Kimia Pembantu
Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah konsumsi bahan kimia
adalah konsumsi pupuk, nilai
pembantu dan produksi CPO.
8. Efisiensi Penggunaan Energi
Variabel yang diukur dalam menentukan efisiensi penggunaan energi yaitu
energi input, energi berguna, kapasitas pengukuran dan kapasitas terpasang.
48
F. Metode Pengumpulan Data
1. Pengumpulan Data Primer
a
Pengamatan dan pengukuran pada pompa penyiraman di pembibitan
main nursery, data yang diambil yaitu spesifikasi alat, jumlah konsumsi
solar, waktu penggunaan alat dan jumlah bibit yang tersiram.
Pengukuran dan pengamatan pada proses pengangkutan kelapa sawit, data
yang diambil yaitu jenis kendaraan, konsumsi solr, jarak tempuh, jumlah
trip pengangkutan, jumlah TBS terangkut, jumlah tenaga kerja dan jam
kerjanya.
Pengamatan dan pengukuran pada peralatan yang mengkonsumsi energi
listrik, data yang diambil yaitu spesifikasi alat, tegangan, arus dan waktu
operasi alat.
Pengamatan dan pengukuran pada mesin pembangkit tenaga diesel, data
yang diambil yaitu spesifikasi alat, konsumsi solar, waktu penggunaan,
output daya listrik.
Pengamatan dan pengukuran pada penggunaan steer loader untuk
memindahkan tandan kosong ke truk pengangkut, data yang diambil
yaitu jenis alat, Konsumsi solar, waktu penggunaan, jumlah tandan
kosong dan jumlah operator.
Pengamatan dan pengukuran proses pengangkutan tandan kosong dari
pabrik ke kebun, data yang diambil yaitu jenis kendaraan, konsumsi
solar, jarak tempuh, jumlah trip pengangkutan, jumlah tandan kosong
terangkut, jumlah tenaga kerja dan jam kerjanya.
Pengamatan dan pengukuran pada boiler, data yang diambil yaitu jumlah
serat dan cangkang yang dihasilkan, jumlah serat dan cangkang yang
dikonsumsi boiler, nilai kalor cangkang dan serat, spesifikasi boiler,
waktu operasi boiler, suhu uap, tekanan uap, laju uap, subu air umpan,
lju air umpan, suhu BPV, tekanan BPV, spesifikasi turbin, daya ouput
turbin serta jumlah produksi CPO yang dihasilkan pada kurun waktu
operasi boiler.
49
h. Pengamatan dan pengukuran pengeringan biji sawit di nut silo dan_inti
sawit di kernel data yang diambil yaitu jenis dan jumlah alat yang
dipakai, suhu lingkungan (bola kering dan bola basah), suhu udara panas
(bola kering), suhu outlet pengering (bola kering), suhu uap heater,
jumlah bahan yang dikeringkan, waktu pengeringan, kadar air sebelum
dan sesudah dikeringkan.
2. Pengumpulan Data Sekunder
a. Catatan kegiatan budidaya pada bagian tanaman meliputi Iuas laban,
jenis kegiatan budidaya, produksi TBS, penggunaan tenaga kerja, jam
kerja, penggunaan pupuk, pestisida dan data penggunaan solar.
b. Catatan kegiatan pada bagian pengolahan dan bagian teknik meliputi
kapasitas pengolahan, jumlah produksi CPO, kegiatan pengolahan, waktu
penggunaan alat dan data fisik peralatan dan mesin yang digunakan
dalam proses produksi yang digunakan untuk melengkapi data primer
dan kebutuhan pethitungen.
c. Catatan kegiatan Laboratorium, meliputi jenis dan jumlah alat yang
dipakei, waktu penggunaan alat, data penggunaan bahan kimia pembantu
dan neraca masa (material balance).
G. Perhitungan dan Analisa Data
Perhitungan terhadap masukan energi yang digunakan, dilakukan
dengan memasukkan variabel pada persamaan yang telah ditentukan dan
semua satuan dikonversikan pada satuan MJ/kg CPO.
Persamaan yang dipakai dalam perhitungan adalah sebagai berikut :
1. Energi Manusia
Besamya energi manusia yang dibutuhkan pada kegiatan proses
budidaya tanaman kelapa sawit dihitung dengan persamaan (Anwar, 1990
dalam Sholahuddin, 1999) :
(AKOxTxNem)
Jtbs
Etml = (4.1)
50
Sedangkan jumlah energi manusia yang dikonsumsi dalam kegiatan proses
produksi CPO di pabrik didekati dengan persamaan berikut :
(HKOxTxNem)
Jepo
Sehingga total konsumsi energi manusia yang digunakan untuk memproduksi
Em’ we f4.2)
tiap kilogram CPO adalah :
(4.3)
Etm(tot) = = + Bim
dimana :
Etm(to) = Konsumsi energi manusia total untuk memprodul
(Milkg CPO)
Etm 1 = Konsumsi energi manusia selama kegiatan budidaya
tanaman kelapa sawit (Mi/kg TBS)
Eun2 = Konsumsi energi manusia selama kegiatan pengolahan TBS
(Milkg CPO)
HKO = Hari Kerja Orang (hari)
T = Waktu orang bekerja (jam)
Nem Nilai kalor tenaga manusia (MI/Jam), berdasarkan Stout (1990)
Hibs ~ Jumlsh produksi TBS (kg)
Jepo = Jumlah produksi CPO (kg)
Rd = Rendemen (%)
2. Energi Listrik
Besamya energi listrik yang digunakan untuk memproduksi tiap kg,
CPO didekati dengan persamaan sebagai berikut (Anwar, 1990 dalam
Sholahuddin 1999):
Pxtxn (44)
Jepo 7
Elk
Nilai daya listrik untuk fasa satu dihitung dengan menggunakan
persamaan (PT. Koneba, 1987 dalam Sholahuddin, 1999) :
P=VICos@
Untuk menghitung nilai daya listrik fasa 3 digunakan persamaan (PT.
Koneba, 1987dalam Sholahuddin 1999) :
445)
P=VICos0 V3
Si
dimana :
Elk = Energi listrik yang digunakan untuk memproduksi tiap kg CPO
(Mi/kg CPO)
t = Waktu pemakaian alat jam)
= Bfisiensi alat, dalam desimal
Jumlah produksi CPO (kg/jam)
V = Tegangan (volt)
I = Amus (ampere)
Faktor daya
Daya motor (mesin) terukur (kW)
P =
3. Energi Bahan Bakar Minyak (Solar)
Jumlah energi solar yang digunakan pada kegiatan budidaya tanaman
dan pengangkutan TBS dihitung dengan persamaan (Anwar, 1990 dalam
Sholahuddin, 1999) :
Kix Neb (i)
Jibs
Sedangkan dalam kegiatan pengolahan untuk memproduksi tiap kg CPO
Ebml= >) (4.7)
digunakan persamaan :
Kix Neb(i)
Ebn2= > Teo
v4.8)
Sehingga total energi bahan bakar untuk memproduksi tiap kg CPO dapat
dijabarkan sebagai berikut :
Ebm(tot) = ae + Ebm2
dimana :
Ebm1 = Energi bahan bakar solar pada kegiatan budidaya tanaman dan
pengangkutan TBS dan pemeliharaan tanaman (Mi/kg TBS)
Ebm2 = Energi bahan bakar solar pada kegiatan pengolahan TBS di
pabrik (MI/kg CPO)
Ebm(tot)= Energi bahan bakar solar total untuk memproduksi CPO tiap
kg (Mi/kg CPO)
Ki = Konsumsi bahan bakar solar pada kegiatan budidaya tanaman
yang ke-I (Itjam)
Kj = Konsumsi bahan bakar solar pada kegiatan pengolahan TBS
yang ke-j (Ivjam)
Neb = Nilai kalor bahan bakar solar tiap liter ( 47.78 Milt, Cervinea
dalam Pimentel, 1980).
Stbs Produksi TBS (kg)
Jepo = Produksi CPO (kg)
i 1,2,3.....
Rd Rendemen (%)
52
4, Energi Bahan Bakar Pada Boiler
Jumiah energi biomassa yang digunakan untuk bahan bakar pada boiler
| Pemb. Pre mussery
So= 000010
a= 0.00399
coos) = | Pemb. Main nursery
$0 =001090 I
Ma 000220
Meroow || Pers, Lahan
a= 000113
perggea Ll Penanaman
Ma =003690
ya =oase | | Pem. TBM
Poise t+ Pem. TM
| Pemanei
‘Ma = 0.02800 a
Meonoel Penyediaan Ma= 000050
Pepe} L_>| Pengangkutan TBS ‘Air Li 0028
- Bengkel Ma= 0.93200
me-oooist 15 Penerimaan Buah Li S0se60
Li o07s
—— 4 ere
|_| Latoratorium ] Ui" = 0.00067
i» 000% Perebusan
i Penanganan Ma 0.00030
Penebahan “Limbah Li =001750
1 Penyedi ‘Ma = 0.00070
Pengempaan "enyediaan 50 0.1098
sgemp: Energi Li =00398
Bi =99200
Pemumian Peng. Biji
a= 0.00100 Ma= 000670
Li =006150 UF = o.10690
Ket: Ma : Energi biologis mannsia (Mi/kg CPO) Li
Pu: Energi pupuk (MJ/kg, CPO) Bi
So. : Energi solar (MJ/kg CPO)
Gambar 12. Aliran Energi Pada Produksi CPO di UU Rejosari”
Energi listrik (MI/kg CPO)
Energi biomassa (Mi/kg CPO)
61
Tabel 17. Konsumsi Energi Manusia Pada Setiap Tahapan Produksi.
Kegiatan Konsumsi energi | Persentase | Persentase
(Milkg CPO) tethadap Total (%)
jumlah (%)
A. Budidaya TL74
= Pembibitan pre mursery 0.00049 036
~ Pembibitan main nurserry 0.00399 2.92
-Persiapan Jahan 0.00220 1.61
=Penanaman 0.00113 0.83
~Pemeliharaan TBM 0.03980 28.49
~Pemeliharaan TM 0.08980 65.78
Jumlah 0.13650 100
B. Pemanenan 0.02800 100 14.72
C. Pengangkutan buah 0.00960 100 5.04
D. Pengolahan TBS 5.54
~ Penerimaan buah 0.00151 1431
= Perebusan 0.00034 3.18 |
= Penebahan 0.00067 6.35
~ Pengempaan 0.00034 3.18
=Pemurnian minyak 0.00100 9.48
= Peng. Biji 0.00670 63.51
Tumlah 0.01055 100
E, Sarana pendukun; 2.96
~ Penyediaan air 0.00050 892
= Penyediaan energi 0.00067 11.90
= Penanganan limbah 0.00059. 10.43
= Laboratorium 0.00067 11.87
~Bengkel 0.00320 56.86
TJumlah 0.00563 100
Total 0.19028 100 100.00
Jumlah penggunaan tenaga manusia untuk kegiatan budidaya di UU
Rejosari lebih Kecil jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia di
pabrik kelapa sawit (PKS) Kertajaya PTPN VIII (Sholabudin, 1999) yaitu
sebesar 2.1624 MJ/kg CPO. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis
pekerjaan yang dilakukan misalnya untuk persiapan lahan di PKS Kertajaya
masih dilakukan manual, sedangkan di UU Rejosari sudah dilakukan semi
mekanis. Di UU Rejosari persiapan Jahan dilakukan tanpa olah tanah
sedangkan di PKS Kertajaya dilakukan_pengolahan tanah, sehingga dalam hal
ini konsumsi tenaga manusia menjadi besar. Pada tahapan penanaman di
perkebunan Kertajaya dilakukan pembuatan petakan dan lubang tanam yang
masih dilakukan secara manual.
Untuk kegiatan pengolahan, konsumsi tenaga manusia di UU Rejosari
sebesar 0.01055 MI/kg CPO atau 5.54 % dari total konsumsi tenaga manusia,
dengan tahapan yang paling besar mengkonsumsi tenaga manusia yaitu
pengolahan biji sebesar 0.0067 Mi/kg CPO atau 63.51 % dari konsumsi tenaga
manusia untuk kegiatan pengolahan. Konsumsi tenaga manusia di pengolahan
lebih besar dibandingkan dengan UU Talopino PTPN. VII (Nuryanto, 1998)
sebesar 0.00214 MJ/kg CPO, hal ini terjadi karena jumlah pekerja di UU
Rejosari lebih besar yaitu 66 orang dengan kapasitas 25 ton TBS/jam
sedangkan di UU Talopino, jumlah pekerja yaitu 45 orang dengan kapasitas 30
ton TBS/jam.
Jumlah pekerja yang lebih banyak dengan tingkat produksi yang
rendah akan mengakibatkan penggunaan energi manusia menjadi lebih tinggi.
Jika dibandingkan dengan PKS Kertajaya konsumsi tenaga manusia di
pengolahan sebesar 0.0062 MJ/kg CPO, maka di UU Rejosari, konsumsi tenaga
manusia di pengolahan masih lebih besar hal ini terjadi karena jam kerja di PKS
Kertajaya lebih kecil yaitu 7 jam/HOK, sedangkan di UU Rejosari sebesar 8
Jam/HOK. Jika dibandingkan dengan PT. Condong, Garut (Alfira, 1999),
dimana konsumsi energi manusia untuk pengolahan sebesar 0.02471 Mi/kg
CPO, maka konsumsi energi manusia untuk pengolahan di UU Rejosari lebih
ecil, hal ini terjadi karena jam kerja di PT. Condong Garut sebesar 10
jam/HOK, disamping itu dalam penelitian tersebut kegiatan pengangkutan buah
termasuk kegiatan pengolahan. Untuk sarana pendukung konsumsi tenaga
manusia sebesar 0.0056 MJ/kg CPO atau 2.96 % total konsumsi tenaga
manusia, dengan kegiatan yang paling besar mengkonsumsi tenaga manusia
yaitu kegiatan di bengkel dan bagian teknik sebesar 0.0032 MJ/kg CPO atau
sekitar 56.86 % dari total Konsumsi tenaga manusia di sarana pendukung.
2, Pupuk
Pupuk merupakan bagian energi tidak langsung yang berperan dalam
produksi CPO, khususnya pada kegiatan budidaya. Jenis pupuk yang
digunakan di UU Rejosari yaitu Urea, NPK, Kiesserite, Rock Phosphate (RP),
Muriate of Potash (MoP), Dollomite, SP-36, Za dan Sulfomag. Konsumsi
63
energi pupuk dapat dilihat pada Tabel 18. Dari tabel tersebut_konsumsi energi
pupuk sebesar 4.925 MJ/kg CPO dengan konsumsi terbesar yaitu pada tahapan
pemeliharaan TM sebesar 4.468 Mi/kg CPO atau sekitar 90.72 dari total
Konsumsi energi pupuk. Sedangkan tahapan kegiatan yang paling kecil
mengkonsumsi energi pupuk yaitu yaitu pembibitan pre nursery sebesar
0.00001 MJ/kg CPO atau 0.0002 % dari total konsumsi energi pupuk.
Tabel 18. Konsumsi Energi Pupuk Pada Kegiatan Budidaya
Kegiatan Konsumsi energi (Milkg Persentase
CPO) (%)
~Pembibitan pre nursery 0.00001 0.0002
= Pembibitan main nurserry 0.00557 0.11
- Persiapan lahan 7 -
=Penanaman 0.00340 0.06
= Pemeliharaan TBM 0.44800 9.09
~Pemeliharaan TM 4.46800 90.72
Jumlah 4.92500. 100.00
Konsumsi energi pupuk total di UU Rejosari lebih kecil dibanding
dengan PKS Kertajaya sebesar 10.7901 Mi/kg CPO. Banyak faktor yang
mempengaruhi dalam penggunaan pupuk ini diantaranya jenis tanah, kondisi
tanaman, Kondisi iklim, keterampilan operator dan lain-lain. Dilihat dari jenis
pupuk yang digunakan yang disajikan dalam Tabel 19, maka input energi
pupuk terbesar berasal dari pupuk Za sebesar 2.6 Mi/kg CPO atau 51.17 %
dari total masukan energi pupuk.
Tabel 19. Penggunaan Energi Untuk Masing-Masing Jenis Pupuk yang
Digunakan
Jenis Pupuk Input energi (Mi/kg CPO) Persentase
Urea 1.0260 19.88
NPK 0.0051 0.09
Kiesserite 0.2620 5.08
Rock Phosphate (RP) 0.0935 1.80
Muriate of Potash (MoP) 0.2040 3.95
Dollomite. 0.5640 10.93
SP-36 0.0439 0.85
Za 2.6400 31.17
Sulfomag 0.3200 6.20
Total 4.9250 100.00
64
3. Bahan Bakar Minyak (Solar)
Dalam pembahasan bahan bakar minyak ini, yang akan dibahas yaitu
solar yang digunakan dari kegiatan budidaya sampai kegiatan di penanganan
limbah padat terkecuali solar untuk penyediaan energi yang akan dijelaskan
kemudian, Penggunaan solar pada kegiatan budidaya meliputi kegiatan
pembibitan pre nursery dan main nursery untuk bahan bakar —pompa
penyiraman dan kegiatan persiapan lahan untuk bahan bakar excavator.
Pada Kegiatan pengangkutan buah solar digunakan untuk bahan bakar
truk pengangkut TBS. Sedangkan pada penanganan limbah padat, solar
digunakan untuk bahan bakar steer loader untuk memindahkan tandan kosong
ke truk pengangkut tandan kosong. Konsumsi energi solar di UU Rejosari
disajikan pada Tabel 20. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah konsumsi
solar sebanyak 0.3087 MJ/kg CPO dengan konsumsi solar terbesar yaitu pada
pengangkutan buah sebesar 0.209 MJ/kg CPO atau 67.70 % dari total konsumsi
solar. Sedangkan pembibitan pre nursery merupakan kegiatan yang
mengkonsumsi energi solar terkecil yaitu sebeser 0.00014 Ml/kg CPO atau
0.045 % dati total konsumsi solar.
Pada pengangkutan TBS, jumlah konsumsi energi solar lebih kecil
dibandingkan di PKS Kertajaya sebesar 1.3304 Mi/kg CPO. tetapi lebih besar
dibandingkan dengan di PT Codong Garut sebesar 0.103 Mi/kg CPO. Tingkat
konsumsi yang berbeda dipengaruhi oleh jarak dari kebun ke pabrik serta
kondisi jalannya, kapasitas angkut TBS tiap mobil angkut serta kondisi dari
mobil pengangkut.
Tabel 20. Konsumsi Energi Solar
Kegiatan ‘Konsumsi energi Persentase (%)
(Mifkg CPO)
= Pembibitan pre nursery 0.0002 0.02
=Pembibitab main nursery 0.0109 1.51
~Persiapan_lahan 0.0561 TB
~Pengangkutan TBS 0.2090 29.04
= Penanganan limbah padat 0.0327 4.54
- Penyediaan energi O411L S71
Total 0.7197 100.00
65
4. Pestisida
Jenis pestisida yang digunakan dalam kegiatan budidaya di UU
Rejosari terditi atas fungisida, herbisida, insektisida dan thodentisida.
Fungisida yang digunakan yaitu Dithane M-45 yang dipakai dalam pembibitan
pre nursery untuk mencegah pertumbuhan jamur pada kecambah/ germited
seeds, Herbisida yang digunakan yaitu Round-Up yang digunakan dalam
kegiatan persiapan lahan, pemeliharaan TBM dan pemeliharaan TM untuk
membasmi gulma khususnya rumput ilalang dan rumput Iainnya. Insektisida
yang digunakan yaitu Ripcord, Marshal dan Phyton yang digunakan pada
kegiatan pembibitan, pemeliharaan TBM dan pemeliharaan TM. Pestisida
digunakan untuk memberantas ulat api, ulat kantong, kumbang dan serangga
penggangu Jainnya. Rhodentisida yang digunaken yaitu Tikumin yang
digunakan untuk memberantas tikus.
Konsumsi pestisida yang digunakan hanya dihitung sebagai kebutuhan
bahan untuk tiap 1 ha dan Kg TBS yang dihasilkan karena kurangnya data
pendukung untuk nilai kalor produksi pestisida. Kebutuhan bahan pestisida
tiap kg CPO dapat dilihat pada Tabel 21.
Tabel 21. Konsumsi Pestisida Dalam Kegiatan Budidaya
Kegiatan Nama ‘Pemakaian pestisida Tamilah
(bahan/ha ') (bahan/kg TBS)
~Pemb. Pre nursery |= Dithane M-45 0.002444 kg 3.8% 10" kg
- Ripeord (0.02763 It 43x10" It
= Pemib. Main mirsery | - Marshal 0.06552 k; 1.0x 107 kg
~Per. Lahan = Round Up 0.0865 It 14x10" It
~Pem. TBM =Round Up 0.846 It 13x10" tt
= Marshal 21.067 Tt 33x10" ke
= Tikumin 10316 ke 16x 107 ke
Bem. TM = Round Up 03771 It 59x 107 It
= Ripeord 21.0141 It 32x10" It
= Phyton 2015 1 3.1% 107 kg
= Tikumin 46.904 kg 73x10" kg
5, Bahan Kimia Pembantu
Bahan kimia pembantu yang digunaken dalam kegiatan produksi CPO
di UU Rejosari digunakan untuk penyediaan air baik di external trearment
66
maupun internal treatment. Bahan pembantu kimia juga digunakan di
laboratorium sebagai bahan bantu untuk pengujian mutu hasil produksi.
Pada external treatment bahan yang ditambahkan yaitu tawas yang
berfungsi untuk menjemihkan air, sera Floc 65 yang berfungsi untuk
mempercepat pengendapan bahan-bahan padatan terlarut. Pada internal
ireatment bahan kimia pembantu yang digunakan yaitu WITCO BWT 2200
yang digunakan untuk mengatur alkali air, WITCO BWT 2041 yang digunakan
untuk mecegah terjadinya kerak pada boiler dan instalasi uap dan WITCO
BWT 2430 yang digunakan sebagai dispersan (pengikat oksigen dalam air).
Bahan kimia pembantu yang digunakan di Laboratorium yaitu alkohol,
N-Hexan, Fenoptalin dan NaOH yang digunakan dalam penentuan kadar asam
lemak bebas CPO yang dihasilkan. Konsumsi bahan pembantu kimia yang
dikosumsi hanya dihitung sebagai kebutuhan bahan tiap kilogram CPO yang
dihasilkan, karena kurangnya data pendukung untuk nilai kalor produksi bahan
Kimia pembantu. Jumlah pemaksian bahan kimia pembantu disajikan pada
Tabel 22.
Tabel 22. Pemakaian Bahan Kimia Pembantu Pada Penyediaan Air dan
Kegiatan di Laboratorium
Tempat Nama bahan Jumlah
(bahan Akg CPO)
External treatment Tawas, 2.74 x10 kg
Floe 65 3.97 x10 It
Internal treatment WITCO BWT 2200 2.53 x10~ It
WITCO BWT 2041 7.59% 10> It
‘WITCO BWT 2430, 3.79 x10 It
Laboratorium ‘Alkohol 96% 78x 107 It
N—Hexan 39x10 it
Fenoptalin 3.0x107 It
NaOH 5.0x1077 It
6. Listrik
Input energi listrik pada kegiatan pengolahan dan sarana pendukung di
UU Rejosari_berasal dari generator diesel dan turbin uap tanpa menggunakan
listrik dari PLN. Konsumsi energi listrik untuk produksi CPO dapat dilihat
pada Tabel 23. Total energi listrik yang dikonsumsi yaitu 0.3969 MJ/kg CPO.
67
Tabel 23. Konsumsi Energi Listrik
Kegiatan Konsumsi Eff. | Persentase | Persentase
energi Teknis alat terhadap total (%)
(Mike CPO) |__(%)__|_jumlah (%)
‘A. Pengolahan TBS
~ Penerimaan buah 0.0075 80.06 294
~Perebusan = : =
= Penebahian 0.0253 72.68 9.99
= Pengempaan 0.0520 82.48 20.54
= Pemumian minyak 0.0615 7537 24.29
~Pengolahan bifi 0.1069 7482 42.23
Jumlah 0.2531 7.08 100 CB.T7
B, Sarana pendukun;
~ Penyediaan air o.0218 66.20 15.
= Penyediaan energi 0.0598 65.67, 41.59
= Penanganan limbah 0.0172 BAS 11.46
= Laboratorium 0.0004 36.37 0.29
=Bengkel 0.0446 $9.38 31.02
Jumiah 0.1438 70.21 100 36.23
Total 0.3969 73.65 100
Bagian yang terbesar mengkonsumsi energi listrik yaitu pada
kegiatan pengolahan sebesar 0.2531 NI/kg CPO atau 63.77 % dari total
konsumsi energi listrik. Penggunaan energi listtik secara rinci pada tiap
tahapan produksi CPO di UU Rejosari dapat dilihat pada Lampiran 15.
Konsumsi energi listrik total di UU Rejosari lebih besar dibandingkan
di PKS Kertajaya sebesar 0.1631 dan PT. Condong Garut sebesar 0.4123 MI/kg
CPO tetapi lebih kecil dibanding UU Talopino sebesar 0.2700 Mi/kg CPO.
Banyak faktor yang menyebabkan penggunaan energi listrik berbeda yaitu
tergantung dari kondisi peralatan yang digunakan, cara pengoperasian
peralatan, stagnasi pengolahan dan kapasitas riil pengolahan. Sedangkan jika
dilihat dari tingkat effisiensi motor listrik yang digunakan, effisiensi rata-rata
motor listrik untuk peralatan pengolahan sebesar 77.08 % dan untuk peralatan
di sarana pendukung sebesar 70.21 %. Sehingga effisiensi motor listrik untuk
peralatan yang digunakan di UU Rejosari sebesar 73.65 %. Nilai effisiensi
tersebut lebih besar dibandingkan dengan di PKS Kertajaya 65.89 %. Hal ini
dipengaruhi oleh umur dan kondisi motor listrik yang digunakan.
68
7. Biomassa
Biomassa yang dihasilkan dari pengolahan yaitu serat (fibre) dan
cangkang (shel!) digunakan sebagai bahan bakar untuk boiler. Jumlah serat dan
cangkang yang dihasilkan yaitu sebesar 54623.75kg/hari, dengan komposisi
yaita serat sejumlah 36109.80 kg/hari dan cangkang sejumlah 18514.17 kg/hari.
Data ketersedian bahan bekar biomassa dapat dilihat pada Lampiran 17.
Nilai kalor serat yang diperoleh yaitu 7.96 Mi/kg pada kadar air 41.22
% sedangkan nilai Kalor cangkang yaitu sebesar 16.44 MJ/kg_ pada kadar air
10.85 %, Data hasil pengukuran nilai kalor bahan bakar biomassa dapat dilihat
pada Lampiran 17. Konsumsi bahan baker biomassa riil untuk boiler
didasarkan pada pengamatan bahwa semua cangkang dan serat yang dihasilkan
digunakan untuk bahan bakar boiler, Penggunaan bahan bakar riil dan nilai
‘masukan energinya dapat dilihat pada Lampiran 17.
Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa masukan energi biomassa
sebesar 9,92 Mi/kg CPO dengan komposisi dari serat sebesar 4.82 MI/kg CPO
atau 48,59 % dari total masukan energi biomassa dan cangkang sebesar 5.10
Mifkg CPO atau 51.41 %, Sedangkan dari perhitimgan kebutuhan bahan bakar
boiler teoritis didapatkan kebutuhan bahan bakar teoritis sebesar 41766.71
kg/hari dengan komposisi yaitu serat sejumlah 27607.79 kg/hari dan cangkang
sebesar 14158,90 kg/hari, Dengan masukan energi dari bahan bakar teoritis
sebesar 6,528 Mi/kg dengan komposisi yaitu dari serat sebesar 3.1717 MI/kg
CPO atau 48.59 % dari total masukan bahan bakar biomasse teoritis dan dari
cangkang sebesar 3.359 Mikg CPO atau 51.41 %. Perhitungan kebutuhan
bahan bakar teoritis dapat dilihat pada lampiran 18. Sehingga ada selisih dari
bahan bakar yang digunakan secara riil dengan kebutuhan bahan bakar teoritis
dan akan dijelaskan pada bagian konservasi energi.
8. Aliran Energi pada Sarana Pendukung Penyediaan Energi
Kebutuban energi listrik dan wap dipasok dari sarana pendukung
penyediaan energi, melalui konversi biomassa menjadi uap kemudian uap
menggerakan turbin uap dan mengkonversi uap menjadi listrik. Selain dari
turbin uap energi listrik berasal dari generator diesel. Pemakaian solar untuk
69
bahan bakar generator diesel dapat dilihat pada Lampiran 17. Untuk
memperoleh data tingkat effektifitas penggunaan energi dilakukan dengan 2
cara yaitu menghitung effisiensi riil penggunaan energi yaitu perbandingan
antara energi berguna dengan input energi dan bila data tersebut tidak
diketahui maka digunakan perbandingan anatara kapasites alat/mesin terakur
dengan kapasitas alavmesin terpasang, yang dalam hal ini disebut effisiensi
teknis. Dari hasil pengamatan dan pengukuran di stasiun penyediaan energi
dapat di buat aliran energi yang disajikan pada Gambar 13.
Pada boiler masukan energi berasal dari biomassa sebesar 9.92 Mi/kg
CPO, air umpan sebesar 1.043 Mi/kg CPO, energi listrik sebesar 0.0598 Mi/kg
CPO dan tenaga manusia sebesar 0.00034 Mlvkg CPO. Sedangkan keluaran
dari boiler yaitu uap superheated dengan kandungen energi sebesar 8.231
Mi/kg CPO. Dari hasil tersebut maka effisiensi riil boiler sebesar 74.67 %.
Input turbin uap yaitu uap superheated dari boiler sebesar 8.231
Mi/kg CPO sedangkan outpumnya yaitu uap saturated yang ditampung dalam
BPV dengan kandungan energi sebesar 7.636 Mi/kg CPO dan energi listrik
sebeser 0.3144 MJ/kg CPO, sehingga effisiensi rill turbin uap untuk
menghasilkan listrik yang merupakan perbandingen antara output listrik dari
turbin uap dengan input uap superheated dari boiler (Haywood, 1995) yaitu
sebesar 3.82 %,. Sedangkan jika dilihat dari effisiensi teknis turbin uap maka
effisiensi teknisnya sebesar 54.74 9%,
Pada generator diesel, input energi berasal dari energi solar sebesar
0.41098 Mi/kg CPO serta tenaga manusia sebesar 0,0001675 Mi/kg CPO.
Output yang dihasilkan dari generator diesel tersebut yaitu energi listrik
sebesar 0.1128 Mi/kg CPO, sehingga effisiensi riil generator diesel yaitu
27.44 % dengan effisiensi teknisnya yaitu 42.92 %.
Jumlah energi listrik dati turbin uap dan generator diesel yaitu sebesar
0.4277 Mi/kg CPO dengan perbandingan penyediaan dari turbin uap dan
generator diesel yaitu sebesar 73.63 : 26.37. Kebutuhan energi listrik yang
terukur pada semua peralatan produksi yaitu 0.3969 M/kg CPO.
70
Bioug uevpatuog uniseg epeg Iroug weNTY “ET TeqUTED
P'9E | 9L"E9 Teseqos Stmynpuod vuems UEP WEYE[OSLAd isepeEysUT erEyUE YINSH] UeUNBSuad oseY Oo
LE9T? EEL TwsAqas soWeI0UNS uep den wqny Ere EST [Brows osey ©
% O'T6= PLLZP'O/S696E'O = ANS! WeeunsSuad [ro] YA oO
%8TSL = MST] KO}OW SUD|AL BAO
% Uy = Seeis'est = Joqeroued SINE], Ya ©
%ULPS = 0s6/0¢s = igi sTH}L, BA ©
HWE = TET'8/6VTE'O = WGM TIE BA ©
% PLZ = — LL T'O/8ZIT'O = Jesarp BAO
WLI PL = WOT TES = 2109 INL BAO
Odd BYVCM WeNIEs upEp yndyno uep nduy eng
£1000°0 + BsnUEyAT
oly = eos.
sero
Froleetl cola! STIL: ES
[psonp wIsoy
vLeero
C0000: ESM,
lesto vaplog 3600: EsrT
“unqejodued iseyeisey pOPLEO: HENSET deg way [eeg seen £y0'L + wedumn sry
: 0026's: esseworg,
Sunynpuad euesws -p pao Z000'0 : BSH,
uayeyo8uad isepeisuy
9, Pengeringan di Nut Silo dan Kernel Silo.
Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan pada nut silo make
didapatkan rata-rata suhu lingkungan yaitu 31.33 °C (bola kering) dan 27.33 °C
(bola basah), subu udara setelah dipanaskan 80.17 °C dan suhu udara keluar
pengering (outle) 43.50 °C. Data hasil pengukuran dan contoh perhitungan
pada pengeringan di nut silo dan kernel silo dapat dilihat pada Lampiran 19 dan
Lampiran 20. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan rata-rata_laju
penguapan air sebesar 27.85 kg/jam, laju aliran udara 1832.95 m‘/jam, energi
untuk memanaskan udara 95.47 MJ/jam dan konsumsi uap panas sebesar 0.035
ton uap/jam.
Pengukuran yang sama dilakukan pada kernel silo, hasil yang
diperoleh yaitu rata-rata suhu lingkungan sebesar 30.33 °C (bola kering) dan
26.00 °C (bola basal), suhu udara setelah dipanaskan 81.00 °C dan suhu udara
keluar pengering (outlet) 44.53 °C. Dari hasil perhitungan didapatkan rata-rata
laju penguapan air sebesar 17.92 kg/jam, laju aliran udara 1135.41 m°jam,
energi untuk memanaskan udara 62.93 MJijam dan konsumsi uap panas sebesar
0.021 ton wapfjam. Pada pengeringan di kernel silo, jika dibandingkan dengan
UU Talopino, didapatkan energi untuk memanaskan udara pengering sebesar
407.651 Mi/jam dan di PKS Kertajaya sebesar 264.898 MJ/jam, maka hasil
yang diperoleh yaitu 62.93 MJ/jam di UU Rejosari lebih kecil. Dalam hal ini
perbedaan tersebut tergantung dari Kondisi uap heater , kondisi bahan yang
akan dikeringkan, kondisi lingkungan serta Kondisi dari alat pengering itu
sendiri
B. Peluang Penghematan dan Konservasi Energi
Dari hasil perhitungan Konsumsi energi dan tingkat effektifitas
penggunaan energi yang dilakukan pada proses produksi CPO di Unit Usaha
Rejosari PTP. Nusantara VII (Persero) Lampung Selatan, terlihat bahwa masih
memungkinkan untuk melakukan usaha penghematan energi, terhadap beberapa
masukan energi yang digunakan, Upaya penghematan energi dalam hal ini bisa
dilakukan dengan meningkatkan tingkat effektifitas produksidan tingkat
efisiensi penggunaan energi. Tingkat effektifitas produksi merupakan
2
perbandingan antara kapasitas pengolahan riil dengan kapesitas pengolahan
terpasang. Sedangkan penetuan tingkat effektifitas penggunaan energi
dilakukan dengan 2 cara yaitu menghitung effisiensi riil penggunaan energi
yaitu perbandingan antara energi berguna dengan input energi dan bila data
tersebut tidak diketahui maka digunakan perbandingan anatara kapasites
alat/mesin terukur dengan Kepasitas alat/mesin terpasang, yang dalam hal ini
disebut effisiensi teknis.
Menurut Dirjen Listrik dan Energi Baru, Departemen Pertambangan
dan Energi (1984), pelaksanaan konservasi energi dapat dilakukan melalui cara
(1). Penataan (house keeping) menyangkut peningkatan effisiensi dari proses
dan peralatan yang ada, yang relatif tidak memerlukan investasi dan dapat
dilakukan dalam waktu singkat. (2). Modifikasi dengan investasi sedang
(retrofitting), menyangkut modifikasi dari pabrik/peralatan, termasuk perbaikan
isolasi pipa, tangki serta penambahan alat-alat kontrol. (3). Modifikasi dengan
investasi besar, menyangkut perubahan-perubahan yang besar/modifikasi
menyeluruh dari industri dengan pemakaian teknologi penggunaan energi yang
terbaru,
Kapasitas pengolahan riil yang diperoleh yaitu 339.59 ton TBS/hari
sedangkan kapasitas pengolaban terpasang yaitu 500.00 ton TBS/hari, sehingga
tingkat effektifites produksinya 67.92 %. Dalam hal ini semakin rendah
tag riil produksi akan semakin
kapasitas pengolahan riil berarti produkti
rendah, Pada saat ini usaha untuk meningkatken kapasitas produksi di UU
Rejosari belum perlu dilakukan karena kapasitas riil pengolahan yang masih
rendah,
Tingkat effektifitas produksi sebesar 67.92 %, mengakibatkan pabrik
sering tidak beroperasi karena kurangnya pasokan TBS. Hal ini terlihat dati
adanya selisih hari panen dengan hari olah yang menunjukan adanya
penyimpanan TBS terlebih dulu untuk menunggu jumlah TBS minimal yang
dapat diolah per hari yaitu sebesar 200 ton TBS. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan yaitu dengan semakin meningkatkan pasokan TBS melalui kegiatan
budidaya yang optimal serta terus menjalin kemitraan dengan petani-petani
kelapa sawit.
1B
Pada penggunaan tenaga manusia dalam kegiatan pengolahan, terjadi
pemborosan energi akibat kurangnya pasokan TBS, sehingga jam olah iil
pabrik yaitu 13.768 jem/hari lebih kecil dibanding jam kerja pegewai yainu 16
jem/hari untuk 2 shift kerja. Sehingga dari hal tersebut terdapat selisih sebesar
2.232 jam/hari atau 1.116 jam/shif kerja. Akibat pemborosan waktu tersebut
maka cnergi yang terbuang yaitu 0.00086 MJ/kg CPO atau sebesar Rp. 1.52 /kg
CPO, schingga biaya yang terbuang tiap hari sebesar Rp. 105294.60. Upaya
penghematan dapat dilakukan dengan meningkatkan pasokan TBS, sehingga
jam olah ril dapat ditingkatkan dan pemborosan waktu kerja dapat dikurangi.
Pada sarana pendukung penyediaan energi, pemborosan energi terjadi
karena adanya kelebihan pemakaian bahan baker boiler. Dari hasil perhitungan
antara Konsumsi bahan baker riil dengan konsumsi baban bekar teoriti
terdapat selisih bahan bakar sebesar 12857.25 kg/heri, sehingga dari selisih
tersebut maka energi yang terbuang dari bahan bakar tersebut yaitu 1.95 Mi/kg
CPO. Jika bahan bakar tersebut digunakan untuk mengganti bahan bakar solar,
maka akan dapat menghemat solar sebanyak 293.76 liter/hari atau dalam bentuk
biaya sebesar Rp. 4.62 /kg CPO atau Rp. 320108.44 /hari. Upaya penghematan
tersebut dapat dilakukan dengan mengatur bahan bakar boiler sesuai kebutuhan
is,
dan menampung sisa bahan bakar tersebut untuk digunakan kembali
Penggunaan bahan bakar sisa tersebut dapat dilakukan untuk boiler cadangan
dalam jangka waktu tertentu misal selama 4 hari sekali, sehingga dalam 4 hari
sekali dapat menggunakan 2 boiler secara bersamaan, Penggunaan 2 boiler
secara bersamaan bisa dilakukan setiap hari, tetapi hanya cukup untuk
menjalankan boiler selama 2.96 jam. sehingga jika penggunaannya tiap 4 hari
maka boiler bisa beroperasi selama 11.84 jam.
Pada penggunaan energi listrik, pemborosan energi dapat terlihat dari
adanya selisih dari sumber listrik utama (turbin uap dan generator diesel)
sebesar 0.4277 Mi/kg CPO dengan energi listrik yang terukur pada peralatan
pengolahan dan sarana pendukung sebesar 0.3969 Mi/kg CPO. — Selisih
tersebut merupakan energi yang_hilang (losses) yaitu sebeser 0.0379 Mi/kg
CPO atau sebesar 7.19 % dari total masukan energi listrik. Biaya yang
tecbuang akibat pemborosan tersebut yaitu Rp. 0.68/kg CPO atau
4
Rp. 47 027.14/hari, Upaya yang dapat dilakukan untuk penghematan energi
listrik ini diantaranya melalui pembenahan sistem jaringan dan instalasi listrik,
seperti pengggantian kabel yang sudah tua, karena kabel tersebut mempunyai
nilai resistansi yang tinggi. Modifikasi motor listrik dapat dilakukan untuk
motor listrik yang mempunyai nilai effisiensinya kecil, dengan cara melakukan
penggulungan ulang (rewinding) atau babkan mengganti motor listrik yang
bekerja diluar karakteristiknya, Penghematan energi listrik untuk penerangan
di pabrik dapat dilakukan dengan cara menggunakan lampu sesuai dengan
kebutuhan, seperti mengurangi penerangan ketika tersedia cahaya alamiah,
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam usaha konservasi energi listrik ini
adalah sikap dari operator untuk menyadari pentingnya penghematan energi dan
upaya perawatan serta pemeliharaan semua peralatan secara kontinyu,
Akibat pemborosan energi seperti yang diuraikan di atas maka energi
yang terbuang pada produksi CPO di UU Rejosari_ yaitu 1.98165 MJikg CPO
atau dalam bentuk biaya yaitu sebesar Rp. 6.82 /kg CPO, sehingga dalam satu
hari biaya yang terbuang sebesar Rp. 472475.18. Hasil perhitungan
pemborosan energi dapat dilihat pada Lampiran 21.
Usaha penghematan pada penggunaan uap dapat dilakukan dengan
menggunakan uap sesuai dengan kebutuhan, dalam artian operator bisa disiplin
tethadap standar penggunaan uap. Upaya lain dapat dilakukan melalui
perbaikan instalasi pengelizan uap yang mengelami kebocoran, serta
penggantian beberapa alat ukur uap yang mengalami kerusakan,
15
VI. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit energi yang telah dilakukan di UU Rejosari
PTP. Nusantara VII (Persero) Lampung Selatan diperoleh beberapa kesimpulan
yaitu sebagai berikut :
1. Dari hasil perhitungan terhadap Konsumsi energi, baik terhadap energi
Jangsung maupun tidak langsung dengan tidak memperhitungkan masukan
energi dari pestisida, bahan kimia pembantu dan alat atau mesin yang
digunakan, dibutubkan masukan energi primer rata-rata sebesar 15.7550 MI
untuk memproduksi tiap kg CPO. pada kapasitas pengolehan 25 ton TBS/jam
dan tingkat rendemen 20.89 %, dengan asumsi sistem produksi CPO yang
dianalisis berjalan secara normal dan tidak terjadi perubahan teknologi
produksi.
2. Konsumsi energi primer yang diperlukan tersebut berasal dari input energi
pupuk sebesar 4.925 MJ (31.26 % dari total masukan energi primer), solar
0.7190 MS (4.57 %), biomessa 9.9200 MJ (62.96 %) dan energi biologis
manusia sebesar 0.1900 MJ (1.20%). Berdasarkan tahapan proses produksi,
jumlah energi primer tersebut dibutuhkan pada kegiatan budidaya sebesar
5.1287 MJ (32.56 % dari total konsumsi energi primer), pemanenan sebesar
0.0280 MI (0.19 %), pengangkutan 0.2186 MI (1.40 %) dan pengolahan TBS
serta sarana pendukung sebesar 10.3739 MJ (65.85 %).
3. Konsumsi energi pada pengolahan TBS dan sarana pendukung produksi
setelah energi primer dikonversikan menjadi energi listrik yaitu masing-
masing sebesar 0.2575 MJ/kg CPO dan 0.1820 Mi/kg CPO.
4, Pada pengolahan TBS menjadi CPO, input energi terbesar berasal dari energi
listrik sebeser 0.2530 Mi/kg CPO atau 96.02 % dari total input energi untuk
pengolahan sedangkan tabapan yang paling besar mengkonsumsi energi yaitu
tahapan pengolahan biji sebesar 0.1076 Mi/kg CPO atau 43.11 % dari total
konsumsi energi untuk pengolahan TBS menjadi CPO.
5. Dari aliran energi pada sarana pendukung penyediaan energi didapatkan
effisiensi riil boiler sebesar 74.67 %, effisiensi riil generator diese! sebesar
27.44 %, effisiensi riil turbin uap untuk menghasilkan energi listrik
sebesar 3.82 %. Sedangkan effisiensi teknis yang merupakan perbandingan
antara kapasitas terukur dengan kapasitas terpasang didapatkan cffisiens!
teknis generator diesel sebesar 42.92 %, effsiensi teknis turbin sebesar 54.74
% dan effisiensi teknis rata-rata motor listrik sebesar 73.65 %.
. Energi listrik yang dihasilkan dari sarana pendukung penyediaan energi
sebesar 0.4277 Mi/kg CPO berasal dari turbin uap sebesar 0.31494 Mike
CPO atau 73.63 % dari total masukan energi listrik dan generator diesel
sebesar 0.1128 Mi/kg CPO atau 26.37%, Kebilengan energi listrik dari
input listtik ke peralatan pengguna listrik sebesar 0.0379 Mi/kg CPO atau
sebesar 7.19 % dari total masukan energi listrik. Konsumsi energi listrik pada
instalasi_pengolahan sebesar 0.2531 MJ/kg CPO dan instalasi sarana
pendukung sebesar 0.1438 MJ/kg CPO, schingga rasio penggunaan energi
listrik antara instalasi pengolahan dengan sarana pendukung sebesar 63.76 =
36.24,
Pada proses pengeringan di nut silo didapatkan bahwa laju penguapan air
sebesar 27. 85 kg/jam, laju aliran udara sebesar 1832.95 m°/jam, energi untuk
memanaskan udara sebesar 95.4653 MJ/jam dan konsumsi uap panas sebesar
0.035 ton/jam. Sedangkan pada proses pengeringan di Kernel silo didapatkan
laju penguapan air sebesar 17.42 kg/jam, laju aliran udara sebesar 1135.41
m'/jam, energi untuk memanaskan udara sebesar 62.9332 MJ/jam dan
konsumsi ap panas sebesar 0.023 ton/jam.
. Besamya pemborosan energi yaitu sebesar 1.9816 Mi/kg CPO atau dalam
bentuk biaya yaitu Rp. 6,82 /kg CPO sehingga biaya yang terbuang tiap hari
sebesar Rp. 472475.18. Pemborosan ini berasal dari pemakaian tenaga
manvsia untuk pengolahan TBS, penggunaan serat dan cangkang sebagai
bahan bakar pada boiler serta adanya kehilangan energi listrik.
. Berdasarkan hasil pengamatan, usaha Konservasi energi yang dapat dilakukan
yaitu pertama, dengan semakin meningkatkan produksi TBS sehingga
kepasitas riil pengolahan tiap hari bisa semakin meningkat. Kedua, melalui
pengaturan konsumsi bahan bakar biomassa sesuai dengan kebutuhan. Ketiga,
melalui pembenahan instalasi listrik, memodifiksi peralatan dan mesin
produksi yang bekerja di bawah standar. Keempat, melalui perbaikan instalasi
oa
pipa penyaluran uap yang mengalami kebocoran dan penggunaan uap sesuai
Kebutuhan. Dalam konservasi energi ini usaha yang terpenting yaitu
pemahaman pekerja tentang pentingnya usaha penghematan energi, serta
upaya perawatan dan pemeliharaan harus terus dilakukan secara kontinyu.
8
DAFTAR PUSTAKA
Anonimous, 1993, Vademecum Bidang Pengolahan dan Teknik PT. Perkebunan X
(Persero). Bandar Lampung.
Anonimous, 1993. Vademecum Bidang Tanaman PT. Perkebunan X (Persero), Bandar
Lampung. ;
Anonimous, 1984, Audit energi Sektor Industri. Dirjen Litrik dan Energi Baru.
Departemen Pertambangan dan Energi. Jakarta.
Abdullah, K, 1998, Energi dan Listrik Pertanian. JICA-DGHE. IPB Project ADAET. IPB.
Bogor.
Alfia, Y. 1999, Analisa Energi Pada Proses Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik Kelapa
Sawit PT. Condong Garut — Jawa Barat. Skripsi . Fakultas Teknologi
Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor
Bank Bumi Daya, 1988. Minyak Kelapa Sawit (Suatu Tinjauan Produksi Pemasaran dan
Prospek), BBD. Jakarta.
BPS. 2001. Statistik Indonesia. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
Cahyono, P.D. 1999. Audit Energi pada Proses Pembuatan Gula Tebu di PT. Pabrik Gula
Krebet Baru I, Malang. Jawa Timur. Skripsi . Fakultas Teknologi Pertanian,
Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Djokosetyardjo,M.J. 1993. Ketel Uap. Pradnya Paramitha. Jakarta.
Doering I dan C. Otto. 1978. an Energy Based analysis of Altemative Production
Methods and Cropping System in The Com Belt. Product University,
Agricultural Experimental. Station Lafagete. Indiana.
Endharu, A. 1995. Pengolahan Minyak Kelapa Sawit di Perkebunan Rejosari PT.
Perkebunan X Lampung Selatan. Laporan Praktek Kerja Nyata. Lembaga
Pendidikan Abli Usaha Perkebunan. Yogyakarta.
Fluck. R.C. 1992, Energy in Farm Production, Elsevier Press.
Green, B.M. 1978. Eating Oil, Energy in Food Production. Westview/Boulders.
Colorado.
Haywood,R.W. 1995. Analisis Siklus-Siklus Teknik. UI Press. Jakarta.
evant, AX. 1996, Masukan Energi Dalam Produksi Beras. Disertasi. Program Pasca
Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Lubis, A.U. 1992. Kelapa Sawit (Blaeis guineesis Jack) di Indonesia. Pusat Penelitian
Perkebunan Marihat. Bandar Kuala.
Mustikaningsih, IS. 1996. Analisis Konsumsi Energi Pada Proses Pengolahan Kelapa
Sawit di PKS Kertajaya, PTPN XI Banten Selatan. Skripsi. Fakultas Teknologi
Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Naibaho, MP. 1998. Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa
Sawit. Medan
Nuryanto, A. 1998, Audit Energi Pada Proses Produksi Crude Palm Oil di Pabrik Kelapa
Sawit Usaha Talo Pino PTPN VI (Persero), Bengkulu Selatan. Skripsi .
Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Pimentel, D. 1980. Hand Book of Energy Utilization in Agriculture. CRC Press. Inc.
Bocara. Florida, USA.
Purwadaria, H.K. Nugroho E.A. Suroso. 1990. Termodinamika Teknik. Proyek
Peningkatan Perguruan Tinggi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Rahmat, TA. 2001. Mempelajati Proses Produksi Crude Palam Oil (CPO) di PTP.
Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Bekri- Lampung Tengah. Laporan Praktek
Lapang. Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut
Pertanian Bogor. Bogor.
Santoso, I. 1999. Audit Energi pada Proses Produksi Teh Hitam di Perkebunan Assam
Jayanegara Indah, Sukabumi. Jawa Barat. Skripsi . Fekultas Teknologi
Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Setyamidjaja, D. 1991. Budi Daya Kelapa Sawit, Kanisius. Yogyakarta.
Sholahudin, A.H. 1999, Audit Energi pada Proses Produksi CPO (Crude Palm Oil) di
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kertajaya PTP, Nusantara VII Banten Selatan,
Skripsi . Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Smill, V. 1983. Energy Analysis and Agriculture. Westview Press/Boulders. Colorado.
Stout, B.A. 1990, Hand Book of Energy for World Agriculture. Elsevier Press.
Tumer, W.C. 1982. Energy Management Hand Book. John Willey and Sons Inter
Science Pub. New York.
Vogt, F. 1980. Energy Conservation and Use of Renewable Energies in The Bio
Industries. Pergamon Press. Oxpord.
Wulandani, D. 1991, Studi Model Permintaan Energi Biomassa Rumah Tangga Pedesaan
di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Studi Kasus 4 Desa di Wilayah Kecamatan
Ciomas). Skripsi . Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor,
Bogor.
30
LAMP TLAN
we
ale | 3
ve bandon onpng
ae
Jae HTC
ie
at
iv vsi9 Vsau
TaVSOrdad NOGSH VLGd
iuvSoras vivsn ain
(OU3SURE) IA VHVINVEAN did
(o10s19g) IIA ‘Nd.id Besofey MN weUNgoyog IseyoT Meg “] uENdUET
Lampiran 2. Produktivitas TBS Selama Umur Produktif di UU Rejosari
Umur tanam Produktivitas hasil (ton TBS/tahun)
(hun) | Tr1973_[ Tr1974 | Th197s | Th1976
3 - 9.50 - =
4 10.12 8.40 19.70__|_ 11.60
5 14.20 10.20 32.90 26.30
6 30.80 27.50 42.10 | 33.20
7 49.60 19.00 31,90 | 26.60
8 34.30 26.00 31.40__|_ 26.40
9 41.90 15.40 35.80__| 39.50
10 28.80 19.40 4130 | 48.60
u 39.70 10.20 42.00 __|_ 36.20
12 32.20 20.00 41.90 [34.80
13 46.10 22.30 39.40__| 33.70
14 45.70 10.10 34.40 {42.10
15 30.00 20.00 38.60__|_ 38.20
16 38.70 19.00 41.20 | 34.10
17 34.70 23.10 42.90__| 34.30
18 38.30 23.70 34.40 | 32.00
19 36.40 16.90 33.35_| 23.28
20 33.70 15.50 26.79 | 36.87
21 28.00 14.21 37.10_|_25.16
22 23.96 19.71 26.25 | 18.26
23 32.76 10.44 20.81 [35.99
24 17.86 8.68 36.49 [12.04
25 17.96 17.44 62.47 =
Jumlah 705.85 [386.68 | 813.76 | 649.20
Rata-rata produktivitas TBS selama umur 25 tahun yaitu 638.87
‘Sumber : Bagian Tanamian UU Rejosari
82
277 WUSANTARA Vil (PERSERO)
UNIT USAHA REJOSARY
| Lampiran 3° Bagan Alir Pengolahan
UU Rejosari
SKEMA PROCESSING
S.CAGES AND BOGIES.
S.GANTRY
2. SYERILUIZER 1S.CRUDE On GUTTER
O.HOISTING CRANE
T6.VIBRATING SCREEN
2ENUT BIx
7 Steal io 1
2s nY NUT ELEVATOR,
26.NUT CRACKER
ZULSHELL WINOWING
2B. YERNEL WiNOWING
2B ORY KERNEL ELEVATOR
TERNAL WATER TREATHENT
36, INTERNAL WATER TREATIENT
37, BOWLER STATION
3B, ENGINE ROOM
28. BACK PRESSURE
VESSEL,
Lampiran 4. Data Produksi CPO di UU Rejosari
Tahun | Jumiah | Jumiah produksi | Rendemen
TBS (kg) | CPO (kg) CPO (%)
1990 50850460 | 11354631 DAL
i991 _| 76506250 | 16196058 27
[i992 | ess0s070 | 14655564 71.00
{ 1993 | 70600780 15455308. 21.89
1994 | 71346450 | 15198501 21.30
1995 | 59469560 | 12107869 2036
| 1996 | 70672030 15650431 22.15
[1997 | 67496150 | 14256191 21.09
| 1998 | 50059540 9266833 18.51
[1999 | 87925610 17399311 19.76
2000 | 103408480 | 21002158 2031
I ‘20017 | 31492110 6545877 20.79
20.895
| Rataan
Sumber : Bagian Tanaman UU Rejosari
1). Data tahun 2001 sampai bulan Juni
84
Lampiran 5. Data Waktu Pengolahan di UU Rejosari
Bulan Hasil CPO [Hari olah | Jam ola
(kg) __| (hari/butan) |_(jam/hari)
2000 [Januari |_761490 14 | 1046
Februari 820639 18 8.
Maret 910961 21 8.57
‘April 1306499 22 10.93
Mei 7386455 29 15.11
Juni 2106756 27 14.65
Tuli 1908000 26 14.55
| Agustus 2004029 26 15.59)
September_|_ 2697249 28 18.82
Oktober 2147941 25 17.18
November | 2528954 28 17.96
Desember | 1423185 20 14.36
2001 | Januari 1593571 25 12.45
Februari ‘944028 20 10.15
Maret 718331 19 11.87
‘April 824426 4 11.29
Rata-rata 1567657.25 | 22.625 13.768
‘Sumber : Laporan Manajemen UU Rejosari
85
Lampiran 6. Konsumsi Energi Pada Pembibitan Pre Nursery
Tabel 1. Penggunaan Tenaga Manusia
Nila
Tahapan pekerjaan | HKO/ha! | Pelaksanaan | Total kalor Energi
HKO/ha' | biologis | (MI/Kg CPO)
rmanusia
(4y/jam)
Persiapan lahan _
= Merumpuk 02350 ‘Sekai 02350_| 1.532 18x10"
~Mengayap 0.3307 ‘Sekali 03307 | _1532_ | 2.7 x10"
= Meratakan tana 0.4281 ‘Sekai 04781 | 1.733 38x10
= Buat bedengan L951 ‘Sekali L9ISl | 1.532 15x10
=Buat saluran_air 0.0510 Sekali 0510 | 1.532 41x10
Jumlal 24x10"
Persiapan fanam
=Kumpul top soi! | 0.3384 Sekali o338¢_[_1733_|__ 35x10"
=Isi + susun baby polybag | 0.2914 Sekali 02914 [1.733 2.6x 10°
~Tanam keeambah 0.1654 ‘Sekali 0.1654 | 0.803 69x10"
645 10"
= Penyiraman 0,00502_|~Tiaphari__|~0.34v44_| 1.733 49510"
=Penyiangan dalam (0.02256 | Tiap minggu | ~0.27072_| 1.532 25x10
=Penyiangan luar 0.02068 | Tiap minggu | 0.24816 | 1.352 2.0% 10°
~Penggemburan (0.07869 | Tiap bulan | 0.23607_| 1.532 1.9% 10°
=Pemb. Hama penyakit | 0.02447 | Tiap mingu_| 0.29364 _| 1.532 24x10
=Pemupukan 0.01418 | Tiap 2 minggi | 0.17018 | 1.733, 15%10°
=Pem, Saluran aie 0.0255 | Tiap 2minngu | 0.1530 | 1.532 12x10"
7Seleksi bibit 0.0665 ‘Sekali 0.0665 | _1.532 | _53x10
Jumlah 16x 10"
Pemindahan bibit
~Bonakas bibit 0.05147 Sokal o0sia7_| 1.733 47510
= Angkut bibit 0.02553 Sekali 0.25528_[ 1.733 23x10
Fumlah 18x10
Total 49x10"
Tabel 2. Penggunaan Solar Untuk Pompa
[Keb solar [~ Waktu [Pemakaian | Total [ Jumlah [Keb | Nilaikelor | Energi
(jam) | jalan (hari) | solar | bibit | solar solar Ooh
esahhaxi) (ima) | aay CPO?)
T 7 5 325_| 243559" [0.409 [47.78 | 18x 10
‘Tabel 3. Pemakaian Pupuk
Tenis
Pemakaian total pupuk (kg/ha ")
‘Nilai energi pupuk
‘Energi (Milkg CPO")
Urea
0.023312,
39.86
1.0.x 107
86
Tabel 4. Pengunaan Pestisida
Tenis Nama Pemakaian total pestisida Jumilah
(bahanha ') (bahanv/keg TBS)
Fungisida | Dithane M-45 (0.002444 kg 38x10" ke
Insektisida_| Ripcord 0.02763 43x10" It
Ket,
1), Ha yaitu luas satu ha lahan di kebun, untuk kerapatan tanaman 143 ph/ha, sehingga
kebutuhanbibit di pre mursery setelah dikonversi dengan angka kerusakan tiap ha tanam
diperlukan 188 bibit. Jam kerja tiap HKO_yaitu 7 jam.
2). CPO yang dihasilkan merupakan hasil pengolahan TBS, Dimana TBS yang dihasilkan
‘merupakan hasil budidaya selama 25 tahun untuk Iuasan 1 ha yaitu sebesar 638870 ke dengan
rendemen TBS menjadi CPO yaitu 20.89 %,
87
Lampiran 7. Konsumsi Energi Pada Pembibitan Main Nursery
Tabel 1. Penggunaan Tenaga Manusia
Nila Kalor
Tahapan pekerjaan | HKO/ | Pelaksanaan | Total | biologis
ha! HKOfha! | manusia | (MI/Kg CPO?)
(fia)
‘*Persiapan Iahan
= Merumpuk 1244 Sekali i2aa | 1532 LOx10"
=Mengayap 1.829 Sekali 1.829 | _1.532 15x 10°
= Meratakan tana 0.448 Sekali 0.448 | 1.733 41x10
=Buat bedengan o314 Sekali 0314] 1332 25x10
~Buat saluran ait 0.186 Sekali 0.186} 1.532, 15x10
Sumlah 33x10
+Persiapan tanam
= Kumput top soil 1.695 Sekali 1.695 1733 15x10"
= Pengajiran 0.346 Sekali 0.345 | 0.502 EXESU
= isi tanah ke poly 1.359 Sekali 1359 [1.733 12x 10"
= Susun polybag 0.951 Sekali 0951 1.733 86x10"
= Buat lubang tanam 0.588 ‘Sekali 0.588 | 0.803 25x10
= Tanam bibit O79 Sekali 0.719 | 0.803 30x10"
Tumlab 42x10"
+ Pemeliharaan
=Pem. Saluran air 0.163_| Tiap 2 minngu [2.916 | 1.533 23x10
= Penyiraman 0.080 | Tiap hari__[_17.280_[ 1.733 16x10"
=Penyiangan dalam 0.179 | Tiap 2minggu | 3.222 | 1.532 2.6107
=Penyiangan luar 0.262 | Tiap 2minggu | _4.716 | _1.532 38x10"
~Penggemburan, 0.147 | Tiap bulan [1.323 | 1332 11x 10"
= Mulching 0.405 Sekali 0.405 1.532 33x10"
= Pemupukat 0.077 | Tiap minggu | ~2.772 [1.733 25x10"
=Pemb. Hama penyakit__| 0.087 | Tiap mingu | 2.052_| 1.733 19x 107
~ Seleksi bibit 0.131 | “Tiap 3 bulan [0.393 | 1.532 32x10
Tumlah 31x10
+ Pemindahan bibit
=Bongkar/nuat bibit 1673 Sekai Los 1733, 15x10"
Total 3.99 x10
Tabel 2, Penggunaan Solar Untuk Pompa
Pampa] Ulangan | Keb. ] Waku ] Walt | Total” | Tuma J Keb Energi
ke solar | jalan | operesi | solar(iy) | bibit | solar | (Mikg CPO)
Vier) | jamnari | (hari) (ia
i T 630 [68 [7 25 | rosnaoo_| ross [i240 | aa
z 710_[ 61 | 235 [1661.75 [144035 | 14.00 | S01 x10
3 7a5_| 725 | 225 | 1125563 [144035 | 13.52 |__484x 10
Rata | 705 |_708_| 225 | 1in07.13_| 144035 [13.34 4.7 x10
z H Li 745_[ 225 [1769.63 _|_ $8738 | 5.21 186 107
2 08_[ 65 | 225 | 1242.00__|“se738_|_ 3.66 131 x10
3 0 |720_| 225 | 1396.00|“se738_[3.82 13710
Raia | 09 | 708_| 225 [143588 | 58738 [4.22 1.51 x10
z i 1o_| 720 | 325} 1620.00_| 21078] 12.91 42x10
2 13 | 710_[ 225 | 20762821078 |_16.54 | 5.42 x10
3 10_| 740 |__225 | 1397.30] 21078 | 12.73 | 4.56 10
Raia [aa | 73925 | 176458 [21078 | 14.06 | 4875 10"
Total 9.05_[ 7.08 | 325} 4430759 | 323851 [31.62 [ 1.11 x10
88
Tabel 3. Penggunaan Pupuk
Tenis Penggunaan Nilai energi Energi
total pupuk | pupuk (MJ/kg) (Mikg CPO”)
(kg/ha ')
NPK (15.15.64) 9.515 15.715 Lixio™
‘NPK (12.12.17.2) 38.06 14.159 40x10
Kiesserite 10.38 6 47x 107
Total 5.57 x10
Tabel 4. Penggunaan Pestisida
Tenis Nama Penggunaan Jumlah bahan
total pestisida (ltkg TBS)
(bahan/ha')
Insektisida Marshal 0.06552 Ox 10" kg
Ket.
1) Ha yaitu Iuas satu ha laban di kebun, untuk kerapatan tanaman 143 phvha, sehingga kebutuhan
bibit di main nursery setelah dikonversi dengan angka kerusakan , sehingga untuk tiap ha
‘tanam diperlukan 173 bibit, Jam kerja tiap HKO_yaitu 7 jam,
in merupakan hasil pengolahan TBS.
2). CPO yang di
Dimana TBS yang dihasilkan
‘merupakan hasil budidaya selama 25 tahun untuk luasan I ha yaitu sebesar 638870 ke dengan
rendemen TBS menjadi CPO yaitu 20.89 %.
89
Lampiran 8, Konsumsi Energi Pada Persiapan Lahan
Tabel 1. Penggunaan Tenaga Manusia
HKO | Pelaksa [~ Total _ | Nilai kalor
Tahapan pekerjaan | /ha' | naan | HKO/a' | biologis Energi
manusia | (MJ/Kg CPO)
(Ma/jain)
Merintis/mengukur 3 3 0.502 7.9 x10"
‘Memiancang I 15 15 0.5021 3.9.x 10"
Menumbang, merumpuk 0.243 0.243 1.055, 1.3x 10"
Merencek dan merumpuk 6.5. 6.5 1,532 5.2x10°
Dongke! kayuan 6 6 1.532 48x10"
‘Memaneang IT 3 3 0.502 7.9 x10"
Melubang besar mekanis | 0.486 0.486. 1,055 2.7x10°
Wiping lalang 0.769 0.769 1,532 6.2x 10"
‘Semprot rumpat 4.03 4.08 1.532 3.2x10
‘Memancang Ti 14 14 0.502 3.710"
‘Melubang tanam manual | 6.11 6.11 1.733 5.6 x 107
Total 22x10
Tabel 2. Penggunaan Solar Untuk Excavator
Pekerjaan | Penggunaan ] Konsumsi | Hasil | Solar ] NileiKalor | Energi
Ganvhari) solar (plyjam) | (ha!) solar (MNKg CPO")
(vjam) (wait)
Menumbang 10.5 20 33 50.94 47.78 18x10"
dan merumpuk_
Melubang u ai 28 107.25 47.78 3.8.x 10"
besar
Total 5.6x 10°
Tabel 3. Penggunaan Pestisida
Tenis Nama ‘Penggunaan total pestisida Tumlah bahan
(tha) (lkg TBS)
Tnsektisida [Round Up 0.0865 14x10" Ie
Ket
1) Ha yaitu luas satu ha Jahan di kebun, untuk kerapatan tanaman 143 ph/ha. Jam kerja tiap HKO
yaitu 7 jam.
2). CPO yang dihasilkan merupakan hasil pengolahan TBS. Dimana TBS yang dihasilkan
‘merupakan hasil budidaya selama 25 tahun untuk luasan 1 ha yaitu sebesar 638870 kg dengan
rendemen TBS menjadi CPO yaitt 20.89 %.
90
Lampiran 9. Konsumsi Energi Pada Persiapan Tanam dan Penanaman
Tabel 1. Penggunaan Tenaga Manusia
Tahapan pekerjaan | FIKO/] Pelaksa [Total Nilai Kalor
ha! | naan | HKOMa' | diologis mam
(MS/jam)
‘Aplikasi tandan Kosong | 788 | Sekali_| 7.88 1.733.
‘Menaman LCC 3.07 | Sekali | 3.07 0.803,
Penanaman 657 | Sekali_ | 6.57 0.80.
Total
‘Tabel 2. Penggunaan Pupuk
Tenis ‘Penggunaan | Nilai energi Energi
total pupuk ) pupuk (Myke) (Milkg CPO?)
(kg/ha “)
Rock Phosphate 74.819 544 3.0.x 107
‘Tandan koson; 3515.08, - -
Total 30x10
Ket
1) Ha yaitu luas satu ha lahan di kebun, untuk kerapatan tanaman 143 ph/ha, Fam kerja tiap
HKO yaitu 7 jam,
2), CPO yang cihasitkan merupakan hasil pengolahen TBS. Dimana TBS yang dihasilkan
‘merupakan hasi! budidaya selama 25 tahun untuk Iuasan | ha yaitusebesar 638870 ke dengan
rendemen TBS menjadi CPO yaitu 20.89 %
an
Lampiran 10. Konsumsi Energi Pada Pemeliharaan TBM.
Tabel I. Penggunaan Tenaga Manusia
Nilai Kalor Energi
‘Tahapan pekerjaan HKO/ | Pelaksanaan Total biologis manusia | (MJ/Kg CPO")
ha! HKO/ha' (Miy/jam)
Pemeliharagan jalan 4 | Tiap 6 bulan 24 1.532 19x10"
Penyulaman 0.375 _| Sekali 0375 0.803 16x10"
Wiping ilalang 039 | Tiap balan 13.68 1.532 11x10
Selective weeding 8.09 | Tiep bulan | 291.24 1.532 23x10"
Bokoran, 3.36__| Tiap bulan | 120.96 1.532 9.7 x10"
Pemupukan 0.75 | Tiap 6 bulan 4.50 1.733 41x10"
“Tunas pasir 1.45 | Tiap 6 bulan [5.075 1,532 41x10" |
Kastrasi 0.68] Dua kali 136 1.532 11x 107
Sensus hama penyakit_| 0.037 _| Tiap hari 26.64 0.502 70x10
Pemb, Hama penyakit_ | 1.75 | Tiep 3 bulan_| 21.00 1.733 19 x10"
Pembuatan TPH 1.50 | Sekali 1.50, 1.532 12x 107
Total 389 x10"
Tabel 2. Penggunean Pupuk
Tenis Penggunaan total | Nilai energi pupuk Energi
pupuk (kg/ha ') (Mi/kg) (Milkg CRO”)
Urea 125.91 59.86 5.6x 10
Rock Phosphate 183.49 54g 75x10
‘Muriate of Potash 682.73, 6.69 3.410
138.09 61.55 64x10
32.01 6 14x10
68.05 9.63 49x10"
407.32 81.20 24x10"
Sulfomag 374.55 14.19 40x10
Total 0.4478
Tabel 3. Penggunaan Pestisida
Tenis Nama Penggunaen total Jumlah bahan
pestisida (bahawha ') (bahan/kg TBS)
Tnsektisida Marshal 21.067 It 33x10" kg
Herbi Round up 0.846 _It 13x10 It
(Rodentisida Tikumin 10.316 kg 1.6x 10% kg
Ket.
1) Ha yaitu luas satu ha lahan di kebun, untuk kerapatan tanaman 143 ph/ha. Jam kerja
tip HKO yaitu 7 jam.
2). CPO yang dihasiikan merupakan hasil pengolahan TBS. Dimana TBS yang dihasifkan
‘merupakan hasil budidaya selama 25 tahun untuk luasan 1 ha yaitu sebesar 638870 ke dengan
rendemen TBS menjadi CPO yaitu 20.89 %. -
92
Lampiran 11. Konsumsi Energi Pada Pemeliharaan TM
Tabel 1, Penggunaan Tenaga Manusia
Nilai kaior | __Bnergi
Tahapan pekerjaan | HKO/ba' | Pelaksanaan Total biologi | (MJ/Kg CPO*)
HKOfha' | manusia
(atvjam)
Pemeliharaan jalan 4.0 | Tiap 6 bulan [1760 1,532 14x10
Wiping ilalang 0.285 | Tiap 3 bulan [25.08 1.532 2.0.x 10°
‘Selective weeding 2.93 | Tiap 3 bulan | ~257.84_[ 1.532 2.1% 10)
Bokoran, 3.19 | Tiap 3bulan | 280.72_[ 1.532 23x10"
Pemupukan 1.19 | Tiap 6 bulan | 52.36 1.733 48x10"
Sensus ama penyakit_ | 0.051__|~ Tiaphari__| 269.28 | 0.502 TIx10™
Pemb. hama penyakit 0.69 | Tiap 6 bulan | 30.36 1.733 2.8 x10"
‘Penunasan 5.72 | Tiap Sbulan | 188.76 | __1.532 15 x10
Pemeliharaan TPH 0.27 | Tiap 6bulan | —_11.88 1.532 9.5% 10"
Total 8.98 x 107
Tabel 2. Penggunaan Pupuk
Tenis Penggunaan total ifai energi pupuk Energi
pupuk (kg/ha ') (Mike) (Mifeg CPO?)
Urea 2172.66 59.86 97x10"
Rock Phosphate 2028.50 5.44 83x10"
‘Muriate of Potash 3425.39 6.69 17x10"
Doliomite 1083.93, 61.53 5.0x 107
Kieserite 517.19 6 2.6% 10"
‘SP- 36 410.85, 9.65 3.9x107
Za 3923.54 81.20 2
‘Sulfomag 2603.38 14.19 28x10"
Total 4.468
Tabel 3. Penggunaan Pestisida
Jenis ‘Nama. Pengunaan total Jumlah bahan_
pestisida (bahan/ha ') (bahan/kg TBS)
Roun up o3771 It 5.9107 It
Ripcord 210147 It 3.2x10" It
Phyton 2.015 it 31x10" kg
Tikumin 46.904 kg 73x10" kg
Ket.
1) Ha yaitu Iuas satu ha Jahan di kebun, untuk kerapatan tanaman 143 ph/ha.
2). CPO yang dihasilkan merupakan hasil pengolzhan TBS.
Dimana TBS yang dihasilkan
merupakan hasil budidaya selama 25 tahun untuk luasan 1 ha yaitu sebesar 638870 kg dengan
rendemen TBS menjadi CPO yaitu 20.89 %,
93
Lampiran 12, Konsumsi Energi Pada Pengangkutan TBS
Tabel 1. Penggunaan Tenaga Manusia
Jumiah TBS Nilai kalor
Ulangan | (ke/hari, truk) | HKO! biologis manusia_| Energi (MJ/kg CPO?)
(MiV/jam)
1 22650 3 1.733 76x10"
2 16230 3 1.733 11x10
3 12420 3 1.733 14x10"
4 19050 3 L733 9.1 x10"
3 18450 3 1.733 Sax 10"
6 15960 3 1.733 11x10
Ratan 17460 3 1.733 0.0096
Tabel 2. Penggunaan Solar
Ulangan | Jumlah TBS | ?Penggunaan | Nilai kalor Energi (Mi/kg CPO")
(ke/bari. uk) | solar (lt) _|_ solar (Mit)
1 22650 12. 4178 127x107
2 16230 98 47.78 138x107
3 12420 147 47.78 2.71 x10"
4 19050 19.6 47.78 235x107
5 18450 13.7 47.78, 1.69 x 10"
6 15960) 14.1 47.78 3.02 x 107
Ratan 17460 14.08 47.78 0.2096
Ket.
1), Jumlah jam kerja tiap HKO yaitu 8 jam.
2), Jumlah produksi CPO merupakan hiasil pengolahan TBS dengan rendemen TBS menjedi CPO
sebesar 20.89 %.
94
Lampiran 13. Konsumsi Energi Manusia Pada Pengolahan TBS Menjadi CPO
Nilai Energi
Jumlah Produksi CPO. kalor (Mi/kg CPO)
Tempat tenaga (kg CPOfhari) | biotogis
I manusia
(Mijiam)
Penerimaan buah, 9 69287.50 0,725 1.51 x10"
Perebusan 2 69287.50 335x107
Penebahan 4 | 69287.50 6.70 x 107
Pelumatan dan pengempaan 2 | 6928750 3.35% 107
Pemurnian 6 (69287.50 1.00 x 10
Pengolahan bij 4 (65287.50 670x107
Total 7 a 4.51 x10
Ket
1), Tenaga kerja per hari terbagi menjadi 2 shift kerja dengan waktu kerja tiap shiffyaitu 8 jam.
Lampiran 14. Konsumsi Energi Pada Sarana Pendukung.
Tabel 1. Penggunaan Tenaga Manusia Pada Penyediaan Air
Tempat Jumlah | Produksi CPO | Nilai kalor Energi
tenaga kerja | (kgCPO/hari) | biologis manusia | (Mi/kg CPO)
hati ' (Maja)
Raw water 2 69387 54 0.725 167x 10,
External treatment 2 9287.54 0.725 1.67% 10"
Internal treatment 2 69287.54 0.725 167x107
Total 5.02 x10"
Tabel 2. Penggunaan Tenaga Manusia Pada Penyediaan Energi
Tempat Jumlah Produksi CPO Nilai kalor Energi (MJ/kg
tenaga kerj (kg CPO/hari) | biologis manusia CPO)
thari' (Miyfjam)
Boiler 4 69287.54, 0.725 3.35.x10"
Ruang mesin 4 69287.54 0.725, 3.35 x10"
Total 6.70 x 10
‘Tabel 3. Penggunaan Tenaga Manusia (Operator) Pada Steer Loader
Hari] Jumlah | Jumlah ) Produksi Jam | Nilaikelor | Energi
TBS (ke) | tandan | CPO Kerja | biologis | (Marke
Kosong | (kg CPO) Gam) | manusia Po)
kg) (vifjam)
1_| 2498006329952 | Si95.71 [1 35 0.725 | 49x10"
2 [325650 ['92519.71 | 82519.71 | 1 45 0.725 | 48x10
3 [271325 | 6875376 | 68753.76 | 45 0.725 58x10"
Retaan | 282258.33 | 71524.26 | $8977.95 | 1 417 0.725__[ 3.16 x10"
‘Tabel 4. Penggunaan Tenaga Manusia (Supir) Truk Pengangkut Tandan Kosong
Tai] Twk ] Jumlah | Tumlah | Jam | Produksi | Nilaikalor | Energi
tandan | pekerja | kerja | CPO biologis | (Milka CPO)
kosong Gam | (kgcPO) | manus
(eg) (iijam)
T [31400 7 =| se9212 [0.795 22x10
2 sia99 [1 7 | 26303.59 [0.725 19x10"
z 1_| 48520 [1 9 | 36710.68- [0.725 13x10"
3 [38060 [1 # [3133413 [0.795 1.910"
Z 1 [32985 [1 75_[ 279897 [0.725 21x10"
2358501 9 | 9494.42 |__ 0.725, 22x10"
Ratan 35785 1 8.08 29488.98 0.725 2.0 x 10"
96
Tabel 5. Penggunaan Bahan Kimia Pembantu Dalam Penyediaan Air
Pekerjaan ‘Nama baban | Pemakalan | Jumlsh Tunnla balan
bahan | produksi (ke | (bahan /kg CPO)
(eabanfaet) | “ cPonai
Extemal Geatment | Tawas 18.97 kg | 09387.54 | 2.74x 10 hg
Floe 65 0275 9287.54 [397x101
Ttemal weatment_| WITCO BW 2200_| 1.755 28754 |—2.53x107 1
WwircoBWwr20a1_| 5.265 | 6987.54} 759x107
witcoBwr2430 [2.632 | 287.54 | 3.79107
‘Tabel 6. Penggunaan Solar Untuk Steer Loader
Hari | Sumfah tandan] Jumlah CPO] Pemakaian | NilaiKalor | Energi (ig
kosong (kg) eg) solar()_|_solar (Mt) Poy
T (6329932 $2195.71 21 47.78 19x10
2 $2519.71 68044.81 23 4778 18x10
3 (8753.76 56693.39 27 4778 23107
Rataan_| 7157134 38977.96 24 4778 20% 10
Tabel 7. Penggunean Solar Untuk Truk Pengangkut Tandan Kosong
Hari [Tak] Jumiah wanda] Jomlah | Pemakaiaa | Nila Energi
ke |“ kosong(ke) | CPO(kg) | solar) | kalor | (ws/kg CPO)
solar
i 7 3100 | 35593. | 177 33x10
2 31890 | 26303.50 [182 33x10
z ni 44520 | 36710.68 | 228 30x10"
z 38060 | 3133413 | 206 31x10
3 1 32985 | 2798.97 | 154 27x10
2 35850 | 29494.42 | 187 30x10"
Ratan 35785.67 [3948898 | 189 307x107
Tabel 8. Penggunaan Tenaga Manusia Pada Penanganan Limbah Cair
Tempat Tanaka tenaga | Produkal | Nill Falor Energi
Kerja as cro biologie (Miike CPO)
(&gCPOMari) | manusia
(jam)
‘Penanganan Timbah cair 4 69287.54 0.725 335x107}
Tabel 9. Penggunaan Tenaga Manusia di Laboratorium
Fempat Tumnlah tenaga | roduksi eg | Nila kalor Energi
kerja hari | CPOMhariy | biotogis (Mitkg, CPO)
(Misjax 7
Laboratorium z BTS 075 Saxo
97
Tabel 10. Penggunaan Tenaga Manusia di Bengkel dan Bagian Teknik
"Tempat imnlah tenaga | Produksi__) Nilai Kelor | Energi (MiVkg
kerja ari’ | (kg CPOMari) | biclogis CPO)
manusia
(Mifjam)
Bengkel dan bagian 38 9287.54 072s 3.20% 10
teknik
‘Tabel 11, Penggunaan Bahan Kimia Pembantu di Laboratorium
‘Nama bahan Pemakaian Jumlah produksi Tumilah bahan
Dahan (ke CPOmari) (t/kg CPO)
(fsari)
‘Alkwohol 96% 0.54 9287.54 78x10"
N= Hexa 0.27 (9287.54 3.9 x10
Fenoptalin 0.21 69287.54 30x10"
‘NaOH 0.035 (9287.54 5.0% 10"
Ket:
1), Tenaga kerja. per hari terbagi menjadi 2 shift kerja dengan waktu kerja tiap shiff yaita 8 jam,
kecuali untuk bagian bengkel dan teknik hanya T shift
98
66
SS a TE aE T Tat0> OS
solsee [wer [eso | esei_| nee | ope | one re wet 1 ane aoa =
orsg1 [eet | se09 Paueer [es eos] one wz z BIRT
AUR
SOINOES we coy
Soler y |For | 266. 6 ore | ae 5 z z ea Ta ap =
LoINrs | se01 | 60-9 ‘ost [ewe | ose, oe it i Tan LI
olxou | reo [sce ose [ore | one, oe SI r Taasar Sarg
Ser [ror [esis za sre_| oie, as ve z Tan =
oz | aeor_[oeee oss | y60¢ [ove sth | sew z Saud aos
Xe | ere p16 ree [enue |__ose Pr aot z ‘aiaBi=
Set [rel sc68 eee__[ 906] one ZL 36 i TS TTP =
wisst | eFel| wT6 eae__| 9 | —o9e ve ‘orr i aodDia ig
to + Cc aT wap UR
Eee we C
Ona Ise sae | ona aa aes aT
a) 298 see | o6ur [ae Fee Tor sataawoD rau
Se Z046. ‘ost [aes [oe TL Toa) 20%. Gong.
S06 L086 ‘988 [arse] — ose, 50
¥ 96 2635 ose [ose] — 09 ¥ pT
rN 9 109s, se__| sor [ove zz aan B64 201
INE sete $8 sco | ose. ZI fH w010
O1X6F BEE ‘ose [ae [one zh us} OTe
DEESFL ae
2OrS0F ef. one ore a, 13E
ON cee [ovse eng [sae cra | ose, ia ou
Sores sco oses [656 [tas [ost] ose, ee ROT
orscy | <900 | ¢rs6 [6901 [oes | oz ose ¥e. or ep
sO1¥ FE bet [oses | a9e00_|—uce | ~s0_| oe zo] 0500 aed
Te aRIEy
ET] TAD wr cy wy] ta
Goap dye) | ste sudo | (| annua ‘suasedior | dussedior | suoseiioy
isu ene | ua] osvar wuss, | say | eed msouyreLy
Odd Iprtoyy SEL weye[OBueg epeg ANSI] UeeUNBBuag “T jequL
yENsYT Wroug uMsuoy, “st wendue]
oor
DEF LIT ey,
OTeL0T Ten
FOES we irr aE od we a TAG ny —
‘ONEE, ses, cro] se GE, S00, 3
Anda mungkin juga menyukai
- Ekstraksi Minyak Terpentin Dari Getah PinusDokumen73 halamanEkstraksi Minyak Terpentin Dari Getah Pinusraymond tambunanBelum ada peringkat
- Air Pengisi Ketel UapDokumen49 halamanAir Pengisi Ketel Uapraymond tambunan100% (1)
- 257 742 1 PBDokumen8 halaman257 742 1 PBraymond tambunanBelum ada peringkat
- Rasncang Alat Pengupas LadaDokumen5 halamanRasncang Alat Pengupas Ladaraymond tambunanBelum ada peringkat
- Perancangan Mesin Penghancur PlastikDokumen10 halamanPerancangan Mesin Penghancur Plastikraymond tambunanBelum ada peringkat
- Rancang Bangun Mesin PasteurisasiDokumen13 halamanRancang Bangun Mesin Pasteurisasiraymond tambunanBelum ada peringkat
- Mekanisasi Proses Pencacahan Bahan Pakan Ternak PDFDokumen6 halamanMekanisasi Proses Pencacahan Bahan Pakan Ternak PDFraymond tambunanBelum ada peringkat
- RANCANG BANGUN Mesin Pengupas Kulit Kopi PDFDokumen98 halamanRANCANG BANGUN Mesin Pengupas Kulit Kopi PDFraymond tambunanBelum ada peringkat
- Buku Pedoman Energi EfisiensiDokumen56 halamanBuku Pedoman Energi Efisiensiraymond tambunanBelum ada peringkat
- Booklet PERENCANAAN EFISIENSI Dan ELASTISITAS ENERGI 2012 - B2TE - FINAL271112 - 3Dokumen16 halamanBooklet PERENCANAAN EFISIENSI Dan ELASTISITAS ENERGI 2012 - B2TE - FINAL271112 - 3raymond tambunanBelum ada peringkat
- Analisa Kerusakan Superheater TubeDokumen4 halamanAnalisa Kerusakan Superheater Tuberaymond tambunanBelum ada peringkat