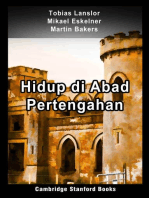3
Diunggah oleh
Abul HasanHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
3
Diunggah oleh
Abul HasanHak Cipta:
Format Tersedia
Melayu sebagai basantara
Lihat pula: Bahasa Melayu § Sejarah
Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bahasa Melayu Klasik
(classical Malay atau medieval Malay). Bentuk ini dipakai oleh Kesultanan Melaka,
yang perkembangannya kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya
terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatra, Jawa, dan Semenanjung
Malaya.[butuh rujukan] Laporan Portugis, misalnya oleh Tome Pires, menyebutkan
adanya bahasa yang dipahami oleh semua pedagang di wilayah Sumatra dan Jawa.
Magellan dilaporkan memiliki budak dari Nusantara yang menjadi juru bahasa di
wilayah itu. Ciri paling menonjol dalam ragam sejarah ini adalah mulai masuknya
kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan bahasa Parsi, sebagai akibat dari
penyebaran agama Islam yang mulai masuk sejak abad ke-12. Kata-kata bahasa Arab
seperti masjid, kalbu, kitab, kursi, selamat, dan kertas, serta kata-kata Parsi
seperti anggur, cambuk, dewan, saudagar, tamasya, dan tembakau masuk pada periode
ini. Proses penyerapan dari bahasa Arab terus berlangsung hingga sekarang.
Kedatangan pedagang Portugis, diikuti oleh Belanda, Spanyol, dan Inggris
meningkatkan informasi dan mengubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu.
Bahasa Portugis banyak memperkaya kata-kata untuk kebiasaan Eropa dalam kehidupan
sehari-hari, seperti gereja, sepatu, sabun, meja, bola, bolu, dan jendela. Bahasa
Belanda terutama banyak memberi pengayaan di bidang administrasi, kegiatan resmi
(misalnya dalam upacara dan kemiliteran), dan teknologi hingga awal abad ke-20.
Kata-kata seperti asbak, polisi, kulkas, knalpot, dan stempel adalah pinjaman dari
bahasa ini.
Bahasa yang dipakai pendatang dari Tiongkok juga lambat laun dipakai oleh penutur
bahasa Melayu, akibat kontak di antara mereka yang mulai intensif di bawah
penjajahan Belanda. Sudah dapat diduga, kata-kata Tionghoa yang masuk biasanya
berkaitan dengan perniagaan dan keperluan sehari-hari, seperti pisau, tauge, tahu,
loteng, teko, tauke, dan cukong.
Jan Huyghen van Linschoten pada abad ke-17 dan Alfred Russel Wallace pada abad ke-
19 menyatakan bahwa bahasa orang Melayu atau Melaka dianggap sebagai bahasa yang
paling penting di "dunia timur".[44] Luasnya penggunaan bahasa Melayu ini
melahirkan berbagai varian tempatan (lokal) dan temporal. Bahasa perdagangan
menggunakan bahasa Melayu di berbagai pelabuhan Nusantara bercampur dengan bahasa
Portugis, bahasa Tionghoa, maupun bahasa setempat. Terjadi proses pemijinan di
beberapa kota pelabuhan di kawasan timur Nusantara, misalnya di Manado, Ambon, dan
Kupang. Orang-orang Tionghoa di Semarang dan Surabaya juga menggunakan varian
bahasa Melayu pijin. Terdapat pula bahasa Melayu Tionghoa di Batavia. Varian yang
terakhir ini malah dipakai sebagai bahasa pengantar bagi beberapa surat kabar
pertama berbahasa Melayu (sejak akhir abad ke-19).[45] Varian-varian lokal ini
secara umum dinamakan bahasa Melayu Pasar oleh para peneliti bahasa.
Terobosan penting terjadi ketika pada pertengahan abad ke-19 Raja Ali Haji dari
istana Riau-Johor (pecahan Kesultanan Melaka) menulis kamus ekabahasa untuk bahasa
Melayu. Sejak saat itu dapat dikatakan bahwa bahasa ini adalah bahasa yang full-
fledged, sama tinggi dengan bahasa-bahasa internasional pada masa itu, karena
memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas.
Hingga akhir abad ke-19 dapat dikatakan terdapat paling sedikit dua kelompok bahasa
Melayu yang dikenal masyarakat Nusantara: bahasa Melayu Pasar yang colloquial dan
tidak baku serta bahasa Melayu Tinggi yang terbatas pemakaiannya, tetapi memiliki
standar. Bahasa ini dapat dikatakan sebagai lingua franca, tetapi kebanyakan
berstatus sebagai bahasa kedua atau ketiga.
Era kolonial Belanda
Majalah[pranala nonaktif permanen] Keboedajaän dan Masjarakat (1939) menggunakan
ejaan Van Ophuijsen.
Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai
untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi karena penguasaan bahasa
Belanda para pegawai pribumi dinilai lemah. Dengan menyandarkan diri pada bahasa
Melayu Tinggi (karena telah memiliki kitab-kitab rujukan), sejumlah sarjana Belanda
mulai terlibat dalam pembakuan bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di
sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu.
Akibat pilihan ini terbentuklah "embrio" bahasa Indonesia yang secara perlahan
mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau-Johor.
Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai
terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia (sebagai Hindia Belanda) mengadopsi ejaan Van
Ophuijsen dan pada tahun 1904 Persekutuan Tanah Melayu (kelak menjadi bagian dari
Malaysia) di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson.[44] Ejaan Van Ophuijsen
diawali dari penyusunan Kitab Logat Melayu (dimulai tahun 1896) van Ophuijsen,
dibantu oleh Nawawi Soetan Makmoer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim.
Intervensi pemerintah semakin kuat dengan dibentuknya Commissie voor de
Volkslectuur ("Komisi Bacaan Rakyat"–KBR) pada tahun 1908. Kelak lembaga ini
menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1910, komisi ini di bawah pimpinan D.A. Rinkes,
melancarkan program Taman Poestaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai
sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Perkembangan program ini
sangat pesat, dalam dua tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan.[46] Badan
penerbit ini menerbitkan novel-novel, seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-
buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit
membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas.
Bahasa Melayu yang disebarkan oleh Balai Pustaka sesungguhnya merupakan bahasa
Melayu Tinggi yang bersumber dari bahasa Melayu Riau-Lingga, sedangkan bahasa
Melayu yang lebih populer dituturkan kala itu di Hindia Belanda adalah bahasa
Melayu Rendah atau bahasa Melayu Pasar. Kwee Tek Hoay, sastrawan Melayu Tionghoa
mengkritik bahasa tinggi ini sebagai bahasa yang tidak alamiah, seperti barang
bikinan, tidak mampu melukiskan tabiat dan tingkah laku sesungguhnya, seperti
pembicaraan dalam pertunjukan wayang yang tidak ditemukan dalam pembicaraan sehari-
hari."[47]
Pada tanggal 16 Juni 1927, Jahja Datoek Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam
pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad, seseorang
berpidato menggunakan bahasa Indonesia.[48]
Anda mungkin juga menyukai
- Sejarah, Fungsi, Dan Kedudukan Bahasa IndonesisDokumen5 halamanSejarah, Fungsi, Dan Kedudukan Bahasa IndonesisNiki CahkediriBelum ada peringkat
- Sejarah Bahasa IndonesiaDokumen4 halamanSejarah Bahasa IndonesiaNonik ArigowoBelum ada peringkat
- Melayu Sebagai BasantaraDokumen2 halamanMelayu Sebagai BasantaraapasihBelum ada peringkat
- Sejarah Bahasa IndonesiaDokumen3 halamanSejarah Bahasa IndonesiaNur UlfiahBelum ada peringkat
- Modul B.indoDokumen204 halamanModul B.indofenny novita100% (1)
- Sejarah Lahirnya Bahasa IndonesiaDokumen5 halamanSejarah Lahirnya Bahasa IndonesiaShella NabillaBelum ada peringkat
- Makalah Perkembangan Bahasa IndonesiaDokumen20 halamanMakalah Perkembangan Bahasa IndonesiaWika WikaBelum ada peringkat
- Sejarah Bahasa IndonesiaDokumen4 halamanSejarah Bahasa IndonesiaAldi SetiawanBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Bahasa IndonesiaDokumen6 halamanSejarah Perkembangan Bahasa IndonesiaRivan Dwi AriantoBelum ada peringkat
- Materi 1Dokumen6 halamanMateri 1d mBelum ada peringkat
- Bahasa IndonesiaDokumen16 halamanBahasa Indonesiavinavina17Belum ada peringkat
- Tugas Sejarah Bahasa IndonesiaDokumen12 halamanTugas Sejarah Bahasa IndonesiaRiani MagdalenaBelum ada peringkat
- Sejarah An Bahasa IdonesiaDokumen12 halamanSejarah An Bahasa IdonesiaNina CokeBelum ada peringkat
- 1 Sejarah Dan Fungsi Bahasa Indonesia Kelas TinggiDokumen30 halaman1 Sejarah Dan Fungsi Bahasa Indonesia Kelas TinggiMaria selvianaBelum ada peringkat
- BMRDokumen8 halamanBMRdwi septiyaniBelum ada peringkat
- Tugas Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesiaaa PDFDokumen19 halamanTugas Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesiaaa PDFluthfia safitriBelum ada peringkat
- Sejarah Indonesia Dan PerkembangannyaDokumen2 halamanSejarah Indonesia Dan PerkembangannyaFransiska DewiBelum ada peringkat
- 75baa Sejarah Bahasa IndonesiaDokumen7 halaman75baa Sejarah Bahasa Indonesianurjanah NacikitBelum ada peringkat
- Draft Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia Sebelum KemerdekaanDokumen2 halamanDraft Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia Sebelum Kemerdekaanekosetyawanto37Belum ada peringkat
- Tugas Meringkas Sejarah Bahasa Indonesia: Andini Septina Zada (23/520955/SA/22624)Dokumen7 halamanTugas Meringkas Sejarah Bahasa Indonesia: Andini Septina Zada (23/520955/SA/22624)AndinBelum ada peringkat
- Sejarah Bahasa IndonesiaDokumen3 halamanSejarah Bahasa IndonesiaIrma Rahmawati100% (1)
- Makalah Kelompok B Indo Part 2Dokumen2 halamanMakalah Kelompok B Indo Part 2Assyifa ArifniBelum ada peringkat
- Perkembangan Bahasa Indonesia Pada Masa Kolonial Dan PergerakanDokumen4 halamanPerkembangan Bahasa Indonesia Pada Masa Kolonial Dan PergerakanRIZKA RAHMANDITABelum ada peringkat
- Materi Ajar Bhs Indonesia TPB 2016 FixDokumen234 halamanMateri Ajar Bhs Indonesia TPB 2016 FixAhmad Alfy WirantanaBelum ada peringkat
- Tongkak MelayuDokumen1 halamanTongkak MelayuANANDA RISKY SANJAYA ANANDA RISKY SANJAYABelum ada peringkat
- Buku Bahasa Indonesia FIXDokumen101 halamanBuku Bahasa Indonesia FIXCynthia LavaniaBelum ada peringkat
- Bahasa Indonesia Zaman KerajaanDokumen9 halamanBahasa Indonesia Zaman Kerajaanmuhammad ikhlasBelum ada peringkat
- Safari 2Dokumen2 halamanSafari 2xrbgc9n4scBelum ada peringkat
- Modul 2 Sejarah Kedudukan Dan Fungsi Bahasa IndonesiaDokumen22 halamanModul 2 Sejarah Kedudukan Dan Fungsi Bahasa IndonesiaSopo JarwoBelum ada peringkat
- Sejarah B-IndDokumen71 halamanSejarah B-IndHasmawiBelum ada peringkat
- Sejarah, Fungsi, Kedudukan, Dan Ragam Bahasa IndonesiaDokumen11 halamanSejarah, Fungsi, Kedudukan, Dan Ragam Bahasa IndonesiaBrentulBelum ada peringkat
- Sejarah Bahasa IndonesiaDokumen2 halamanSejarah Bahasa IndonesiaHanun NadaBelum ada peringkat
- Materi Ajar BHS Indonesia TPB 2016Dokumen232 halamanMateri Ajar BHS Indonesia TPB 2016Annisa NadhaBelum ada peringkat
- Tugas Bahasa IndonesiaDokumen4 halamanTugas Bahasa Indonesiawahyu kurniawanBelum ada peringkat
- Pertemuan 3:: Sejarah Bahasa IndonesiaDokumen23 halamanPertemuan 3:: Sejarah Bahasa IndonesiaIdris SyahrudinBelum ada peringkat
- A. EYD-Tanda Baca-1Dokumen57 halamanA. EYD-Tanda Baca-1Guntur HermawanBelum ada peringkat
- Budaya MelayuDokumen32 halamanBudaya MelayuwanBelum ada peringkat
- Tugas 1Dokumen15 halamanTugas 1Misbahul MunirBelum ada peringkat
- UntitledDokumen2 halamanUntitledMuhammad RiovanzaBelum ada peringkat
- Kerajaa SriwijayaaDokumen9 halamanKerajaa Sriwijayaazonanet perawangBelum ada peringkat
- BM Kuno, Klasik, ModenDokumen27 halamanBM Kuno, Klasik, ModenNi'88% (8)
- Analisis Sejarah Bahasa Indonesia..Dokumen9 halamanAnalisis Sejarah Bahasa Indonesia..Takkual TVBelum ada peringkat
- Kampung Pelestarian Bahasa Melayu Logat Riau Kota TanjungpinangDokumen14 halamanKampung Pelestarian Bahasa Melayu Logat Riau Kota TanjungpinangN Che ShiddiqBelum ada peringkat
- Asal Mula Bahasa Dan Bahasa MelayuDokumen3 halamanAsal Mula Bahasa Dan Bahasa MelayuAhmad SaudiiBelum ada peringkat
- Sbi 2Dokumen21 halamanSbi 2Ahsanul HadiBelum ada peringkat
- Hanum Nurhaliza - 173 Bahasa IndonesiaDokumen10 halamanHanum Nurhaliza - 173 Bahasa Indonesiahanum nrBelum ada peringkat
- Materi 02. Fungsi Dan Kedudukan Bahasa Indonesia - FEBDokumen23 halamanMateri 02. Fungsi Dan Kedudukan Bahasa Indonesia - FEBariprobowo3Belum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Bahasa IndonesiaDokumen4 halamanSejarah Perkembangan Bahasa IndonesiaTauvicMichaelangeloIIBelum ada peringkat
- Bahasa-Bahasa WorkDokumen12 halamanBahasa-Bahasa WorkAfniewatie Prillney QuzaBelum ada peringkat
- Perkembangan BahasaDokumen53 halamanPerkembangan BahasaMeghaSalestianiAdzahraBelum ada peringkat
- Bahasa Indonesia Tugas 1Dokumen3 halamanBahasa Indonesia Tugas 1Paskah PanjaitanBelum ada peringkat
- Tokoh BaratDokumen4 halamanTokoh Baratnur liyana syafiqahBelum ada peringkat
- Penggunaan Bahasa Indonesia Di Lingkungan KampusDokumen10 halamanPenggunaan Bahasa Indonesia Di Lingkungan KampusMuhammad Dimas FahreziBelum ada peringkat
- Makalah BahasaDokumen20 halamanMakalah Bahasabagonk kusudaryantoBelum ada peringkat
- Hakikat Bahasa IndonesiaDokumen21 halamanHakikat Bahasa IndonesiaAhmad Yassar Mahdy SantosoBelum ada peringkat
- Sejarah Dan Perkembangan Bahasa IndonesiaDokumen7 halamanSejarah Dan Perkembangan Bahasa IndonesiaDidi ManusamaBelum ada peringkat
- Cikal Bakal Bahasa IndoDokumen10 halamanCikal Bakal Bahasa IndoAinin Ni'mahBelum ada peringkat
- Bahasa Indonesia Adalah Bahasa Melayu Yang Dijadikan Sebagai Bahasa Resmi Republik Indonesia Dan Bahasa Persatuan Bangsa IndonesiaDokumen6 halamanBahasa Indonesia Adalah Bahasa Melayu Yang Dijadikan Sebagai Bahasa Resmi Republik Indonesia Dan Bahasa Persatuan Bangsa IndonesiaMeli Aprilah SPBelum ada peringkat
- Tuliskan Secara Singkat Sejarah Perkembangan BahasaDokumen8 halamanTuliskan Secara Singkat Sejarah Perkembangan BahasadindaryaBelum ada peringkat
- 5Dokumen3 halaman5Abul HasanBelum ada peringkat
- Si KancilDokumen1 halamanSi KancilAbul HasanBelum ada peringkat
- GrafikDokumen1 halamanGrafikAbul HasanBelum ada peringkat
- TRFRTFFDokumen3 halamanTRFRTFFAbul HasanBelum ada peringkat
- BayaDokumen1 halamanBayaAbul HasanBelum ada peringkat
- KancilDokumen1 halamanKancilAbul HasanBelum ada peringkat
- PPPPDokumen4 halamanPPPPAbul HasanBelum ada peringkat
- Fabel 2Dokumen2 halamanFabel 2Abul HasanBelum ada peringkat
- 6666Dokumen1 halaman6666Abul HasanBelum ada peringkat
- BUAYADokumen2 halamanBUAYAAbul HasanBelum ada peringkat
- Fabel Buaya Dan Burung BernyanyiDokumen2 halamanFabel Buaya Dan Burung BernyanyiTriPujiAntoBelum ada peringkat
- Cerita Fabel 2Dokumen2 halamanCerita Fabel 2rifqiBelum ada peringkat
- 5555555Dokumen1 halaman5555555Abul HasanBelum ada peringkat
- 555Dokumen1 halaman555Abul HasanBelum ada peringkat
- 55Dokumen1 halaman55Abul HasanBelum ada peringkat
- 1Dokumen1 halaman1Abul HasanBelum ada peringkat
- 4444Dokumen1 halaman4444Abul HasanBelum ada peringkat
- 1Dokumen1 halaman1Abul HasanBelum ada peringkat
- 4444Dokumen1 halaman4444Abul HasanBelum ada peringkat
- 4444Dokumen4 halaman4444Abul HasanBelum ada peringkat
- 1Dokumen1 halaman1Abul HasanBelum ada peringkat
- AbaDokumen1 halamanAbaAbul HasanBelum ada peringkat