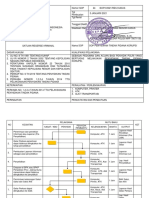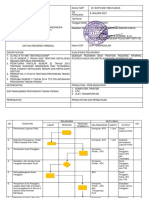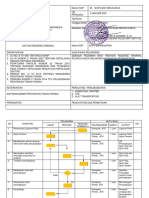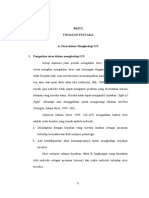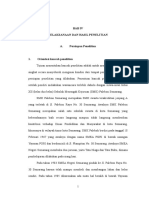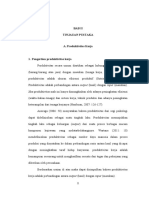Tugas Intisari 2
Tugas Intisari 2
Diunggah oleh
Alex Suseno0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
34 tayangan4 halamanJudul Asli
TUGAS INTISARI 2
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
34 tayangan4 halamanTugas Intisari 2
Tugas Intisari 2
Diunggah oleh
Alex SusenoHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 4
INTISARI
Peluncuran dan Diskusi Buku
“Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan HAM di Abad ke-21”
Oleh:
……………………….
Buku terjemahan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan
Paramadina yang berjudul “Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan HAM di Abad
ke-21”, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penulis asli buku tersebut, yaitu
Kathryn Sikkink, secara garis besar terdiri atas dua hal utama, yaitu asal-usual HAM,
hukum atau norma HAM dan yang kedua adalah efektivitas hukum dan kebijakan HAM.
Terkait dengan asal-usul, hukum atau norma HAM, jika kita melihat sejarah perjuangan
HAM, tampak bahwa HAM merupakan gerakan yang kuat, barangkali gerakan paling kuat
untuk menghadapi berbagai bentuk ketimpangan di dunia, seperti yang didasarkan pada
perbedaan ras, gender, orientasi seksual, dan disabilitas. Karena gerakan HAM telah efektif
dalam mengatasi bentuk ketimpangan lain. Namun di satu sisi, pesimisme terhadap
legitimasi dan efektivitas hukum, institusi, dan gerakan hak asasi manusia belakangan
makin meningkat. Pesimisme ini tidak hanya muncul di kalangan pemerintah dan
akademisi, tetapi juga di dalam gerakan hak asasi manusia sendiri.
Terkait dengan efektivitas hukum dan kebijakan HAM, terdapat dua karakteristik
yang melekat pada masalah-masalah HAM memperumit upaya kita untuk mengukur
efektivitas. Pertama, banyak pelanggaran HAM merupakan bahaya yang tersembunyi dan
karenanya sulit diukur. Gerakan HAM berupaya mengungkap bahaya tersembunyi dan
menjadikannya perhatian dunia. Namun, dalam melakukan hal itu, gerakan HAM dapat
membuat orang berpikir bahwa situasi HAM memburuk padahal nyatanya kita hanya jadi
lebih tahu dan lebih peduli tentangnya. Paradoksnya, keberhasilan gerakan HAM dalam
meningkatkan informasi dan kesadaran dapat digunakan sebagai bukti bahwa hukum dan
aktivisme HAM tidak berhasil, suatu argumen yang didasarkan pada tingginya tingkat
pelanggaran yang berkelanjutan di dunia. Kedua, gerakan HAM bertujuan memperluas
cakupan pelanggaran HAM, sehingga menjadikan standar akuntabilitasnya terus berubah.
Karena itu, HAM adalah target bergerak yang definisinya terus diperluas melalui kerja para
aktivis dan berbagai lembaga. Ini adalah salah satu aspek hak yang paling luar biasa, tetapi
juga menyebabkan masalah pengukuran yang pelik ketika kita hendak membicarakan
kemajuan. Memahami paradoks informasi dan perubahan standar akuntabilitas tidak mesti
membuat kita berpuas diri, tetapi hal ini dapat membuat kita tak terlalu putus asa dan
menjadi pengguna data pengukuran pelanggaran HAM yang lebih bijak.
Buku tersebut sangat terkait dengan fenomena yang terjadi di dunia saat ini. Banyak
kritikus menyatakan bahwa perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia (HAM)
seperti “berjalan di tempat”, bahkan mundur: “Arab Spring” diberangus, perang masih
terus terjadi, dan mutu demokrasi merosot termasuk di AS dan Eropa. Beberapa pegiat
HAM sendiri bahkan terlihat putus asa dan mulai memandang bahwa perjuangan HAM
akan ditakdirkan sia-sia. Dalam buku ini, Kathryn Sikkink membantah klaim-klaim
pesimistik di atas. Berbasis dua dekade lebih risetnya, Guru besar Kebijakan HAM pada
Harvard Kennedy School itu memperlihatkan kuatnya legitimasi dan efektivitas perjuangan
HAM dulu, sekarang, dan di masa depan. Menurutnya, sementara bias kognitif dan
kebiasaan media massa melaporkan hal-hal buruk memang meningkatkan sinisme
mengenai masa depan HAM, riset ilmu-ilmu sosial yang lebih solid menunjukkan
kebalikannya. Institusi HAM pada dasarnya adalah alat dan arena. Meski dapat
dimanfaatkan dengan baik, seperti dalam interaksi antara Dewan HAM PBB dan aktivis Sri
Lanka, institusi itu juga dapat direbut dan ditundukkan oleh rezim represif. Akibat dari
yang disebut oleh salah seorang penulis sebagai “Kurva Belajar Diktator” (Dictator’s
Learning Curve), banyak rezim otoriter jadi lebih cerdik dalam menangkal manuver
kampanye pengembangan demokrasi dan gerakan HAM.
Untuk memecahkan permasalahan manipulasi informasi, dibutuhkan langkah yang
efektif dan juga perlu dipahami sampai ke akar-akarnya. Banyak sekali akar permasalahan
dalam manipulasi informasi ini dan merupakah sebuah tantangan tersendiri dalam
memecahkannya. Diantaranya ada penyebab yang berasal dari individu itu sendiri dan ada
juga yang disebabkan oleh kelompok atau kolektif. Ada penyebab individual, yaitu
penyebab yang berkaitan dengan sifat manusia secara psikologi dan epistemology. Ada
kelemahan kognitif dan krisis pengetahuan yang membuat kita sangat rentan terhadap
manipulasi informasi. Ada pula sebab-sebab kolektif terkait dinamika kehidupan sosial,
krisis kepercayaan terhadap institusi, krisis pers, dan kekecewaan terhadap dunia digital.
Hal tersebut yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan HAM di dunia. Upaya
perlindungan HAM pada dasarnya terus dilakukan dan mengalami peningkatan, akan tetapi
adanya manipulasi informasi menjadikan informasi yang berkembang justru penanganan
masalah HAM jalan di tempat.
Ketika memahami konsep post-truth penting sekali untuk mengeksplorasi
perubahan dengan mempertimbangkan prasyarat psikologis, sosial, teknologi, dan
konteksnya. Menyoal di Indonesia, transformasi media tradisional menuju digital
menduduki posisi vital masyarakat. Seluruh elemen kehidupan sosial telah beresonansi
dengan lingkungan media baru; bahkan media sosial bertindak dominan. Oleh karena itu,
tidak mengherankan bahwa pengaruh munculnya internet dan platform media sosial yang
beragam membuat penyebaran berita palsu semakin intensif (Bhaskaran, Mishra, dan Nair,
2017: 42). Tendensi tren masyarakat ke ranah media sosial telah berkontribusi pada
gencarnya dunia post-truth selama beberapa dekade terakhir. Tampak dari elite politik di
beberapa penjuru dunia yang menggunakan wahana media sosial untuk memanipulasi
paradigma masyarakat melalui fakta alternatif ataupun gosip jahat tentang lawan dengan
asumsi sedikit bukti sehingga mendorong penyebaran kebodohan (Block, 2019: 60). Oleh
sebab itu, terjadi perubahan dalam bidang penegakan hukum terhadap HAM. Insting dan
psikologi netizen yang kerap memainkan politik kebohongan akibat kemalasan nalar yang
menggejala dalam dunia inteletual atau dikenal dengan istilah post-truth (Vilmer et al,
2018). Demokratisasi ruang publik di Indonesia sedang berlangsung, mulai terongrong
oleh devaluasi kebenaran. Kondisi tersebut akan membuka jalan bagi munculnya gerakan
post-truth radikal, seperti kebohongan, obskurantisme, dan ekstremisme. Situasi demikian
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang berusaha melemahkan upaya yang
selama ini dilakukan dalam perlindungan HAM.
Retorika dan omong kosong menjadi pusat alternatif dalam mengambilalih
kesadaran publik. Menurut Fredal (2011: 245) retorika dan omong kosong hadir untuk
berbicara, tidak hanya untuk membentuk dan memengaruhi komunikator, komunikan,
kesepahaman, dan relasi keduanya, melainkan juga membangun elemen masing-masing
secara berkelanjutan melalui negosiasi; menekankan sentralitas respons audiens sebagai
akhir dari setiap pertemuan yang diberikan. Akibatnya, paradigma individu cenderung
bergantung pada ideologi daripada bukti. Omong kosong dan retorika memiliki korelasi
yang kuat, sebab seperti retorika, omong kosong mengandaikan pembicara, pendengar, dan
teks yang memberlakukan karakteristik pertukaran simbolik dari bahasa sedang digunakan.
Keduanya selalu berurusan dengan bahasa yang tidak etis dalam kaitannya dengan
kontinum epistemologis yang mencakup kebenaran. Dimensi kebohongan, kekeliruan, dan
kesalahan ganda diakui sebagai strategi retoris yang salah dan tidak etis karena mereka
dapat dibandingkan secara tidak menguntungkan dengan pendapat yang beralasan dan
kebenaran universal (McComiskey, 2017: 7-8). Salah satu hakikat yang tidak berubah
dalam omong kosong dalam rezim post-truth adalah tidak adanya relasi dengan fakta,
realitas, dan kebenaran di antara retorika politik. Mayoritas publik dianggap sebagai
khalayak lemah karena rentan terhadap omong kosong. Kondisi demikian dimanfaatkan
sebagai wahana destabilisasi atau bahkan penghancuran gagasan kebenaran. Strategi
penekukan realitas tersebut ditempuh secara berulang dalam ranah publik untuk menipu
pendengar yang kurang peduli terhadap kebenaran sehingga mengubah persepsi publik
sesuai dengan persepsi kelompok kepentingan untuk terus melemahkan upaya penegakan
hukum dan perlindungan HAM.
Referensi:
Block, D. 2019. Post-truth and Political Discourse. Switzerland: Palgrave Macmillan.
Fredal, J. 2011. Rhetoric and Bullshit. College English, 73(3), 243–59.
McComiskey, B. 2017. Post-Truth Rhetoric and Composition. Colorado: Utah State
University Press.
Sikkink, Kathryn. (2022). Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan HAM di Abad
ke-21. Alih Bahasa: Irsyad Rafsadie dan Raditya Darningtyas. Jakarta: PUSAD
Paramadina.
Vilmer, Jean Baptiste Jeangene et al. (2018). Information Manipulation : A Challenge for
Our Democracies. Paris: CAPS and IRSEM.
Anda mungkin juga menyukai
- Sop Penyidikan TipidkorDokumen3 halamanSop Penyidikan TipidkorAlex SusenoBelum ada peringkat
- Tugas Konflik Politik-Perubahan Sosial Dan PembangunanDokumen9 halamanTugas Konflik Politik-Perubahan Sosial Dan PembangunanAlex SusenoBelum ada peringkat
- Data Kasus Tppo Tahun 2019 S.D 2024Dokumen19 halamanData Kasus Tppo Tahun 2019 S.D 2024Alex SusenoBelum ada peringkat
- Tugas Hukum Progresif - 3Dokumen4 halamanTugas Hukum Progresif - 3Alex SusenoBelum ada peringkat
- Tugas 1-Ilmu KepolisianDokumen12 halamanTugas 1-Ilmu KepolisianAlex SusenoBelum ada peringkat
- Tugas Review Jurnal Al-RidhoDokumen33 halamanTugas Review Jurnal Al-RidhoAlex SusenoBelum ada peringkat
- Tugas Kliping Korupsi-Perubahan Sosial Dan PembangunanDokumen8 halamanTugas Kliping Korupsi-Perubahan Sosial Dan PembangunanAlex SusenoBelum ada peringkat
- Tugas KriminologiDokumen24 halamanTugas KriminologiAlex SusenoBelum ada peringkat
- Tugas Hukum ProgresifDokumen3 halamanTugas Hukum ProgresifAlex SusenoBelum ada peringkat
- Sop PemanggilanDokumen2 halamanSop PemanggilanAlex SusenoBelum ada peringkat
- Sop Yan Sidik Jari Fungsi IdentifikasiDokumen2 halamanSop Yan Sidik Jari Fungsi IdentifikasiAlex SusenoBelum ada peringkat
- Sop PenangkapanDokumen2 halamanSop PenangkapanAlex SusenoBelum ada peringkat
- 78.04. LAPJU IRWAN 2023 - Perkembangan - KarowassidikDokumen26 halaman78.04. LAPJU IRWAN 2023 - Perkembangan - KarowassidikAlex SusenoBelum ada peringkat
- Laporan Akhir Polres GarutDokumen16 halamanLaporan Akhir Polres GarutAlex SusenoBelum ada peringkat
- BAB II Stres DuksosDokumen19 halamanBAB II Stres DuksosAlex SusenoBelum ada peringkat
- Daftar Persubdit 2023Dokumen21 halamanDaftar Persubdit 2023Alex SusenoBelum ada peringkat
- Kaporlap BhabinkamtibmasDokumen2 halamanKaporlap BhabinkamtibmasAlex SusenoBelum ada peringkat
- 10 - R e S U M eDokumen44 halaman10 - R e S U M eAlex SusenoBelum ada peringkat
- Bab IvDokumen15 halamanBab IvAlex SusenoBelum ada peringkat
- Pra IsiDokumen7 halamanPra IsiAlex SusenoBelum ada peringkat
- Bagian DepanDokumen15 halamanBagian DepanAlex SusenoBelum ada peringkat
- 6 RESUME Saipul Rahman 2Dokumen41 halaman6 RESUME Saipul Rahman 2Alex SusenoBelum ada peringkat
- JURNALDokumen13 halamanJURNALAlex SusenoBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen17 halamanBab IiAlex SusenoBelum ada peringkat
- Bab IvDokumen13 halamanBab IvAlex SusenoBelum ada peringkat
- Daftar Isi, DLLDokumen18 halamanDaftar Isi, DLLAlex SusenoBelum ada peringkat
- Garam NewDokumen50 halamanGaram NewAlex SusenoBelum ada peringkat