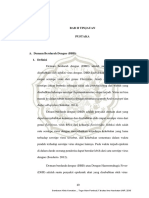0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
62 tayangan18 halamanPanduan DBD: Gejala dan Penanganan
Laporan ini membahas tentang demam berdarah dengue (DBD) yang disebabkan oleh virus dengue. Dokumen ini menjelaskan pengertian, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan penatalaksanaan DBD.
Diunggah oleh
Zaky El-karimHak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
62 tayangan18 halamanPanduan DBD: Gejala dan Penanganan
Laporan ini membahas tentang demam berdarah dengue (DBD) yang disebabkan oleh virus dengue. Dokumen ini menjelaskan pengertian, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan penatalaksanaan DBD.
Diunggah oleh
Zaky El-karimHak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd