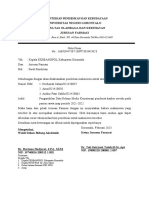Nur'ain Dj. Silaka - Data Kombinasi Tanaman
Nur'ain Dj. Silaka - Data Kombinasi Tanaman
Diunggah oleh
Nur'ain DJ. Silaka0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
4 tayangan7 halamanJudul Asli
Nur'ain Dj. Silaka_Data kombinasi Tanaman
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
4 tayangan7 halamanNur'ain Dj. Silaka - Data Kombinasi Tanaman
Nur'ain Dj. Silaka - Data Kombinasi Tanaman
Diunggah oleh
Nur'ain DJ. SilakaHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 7
URAIAN KOMBINASI TANAMAN HERBAL
DALAM PENGOBATAN TRADISIONAL
1. Jahe (Zingiber officinale)
1.1 Tinjauan Tentang Tanaman Jahe (Zingiber officinale)
Indonesia sangat kaya dengan sumber daya flora. Di Indonesia, terdapat
sekitar 30.000 spesies tanaman, 940 spesies di antaranya dikategorikan sebagai
tanaman obat dan 140 spesies di antaranya sebagai tanaman rempah. Dari
sejumlah spesies tanaman rempah dan obat, beberapa di antaranya sudah
digunakan sebagai obat tradisional oleh berbagai perusahaan atau pabrik jamu.
Dalam masyarakat Indonesia, pemanfaatan obat tradisional dalam sistem
pengobatan sudah membudaya dan cenderung terus meningkat. Salah satu
tanaman rempah dan obat-obatan yang ada di Indonesia adalah jahe (Rukmana,
2000).
Nama ilmiah jahe adalah Zingiber officinale Rosc. Kata Zingiber berasal
dari bahasa Yunani yang pertama kali dilontarkan oleh Dioscorides pada tahun 77
M. Nama inilah yang digunakan Carolus Linnaeus seorang ahli botani dari Swedia
untuk memberi nama latin jahe (Anonimus, 2007).Menurut para ahli, jahe (Zingiber officinale
Rosc.) berasal dari Asia Tropik,yang tersebar dari India sampai Cina. Oleh karena itu, kedua
bangsa itu disebutsebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe, terutama sebagai
bahan minuman, bumbu masakan, dan obat-obatan tradisional. Belum diketahui
secara pasti sejak kapan mereka mulai memanfaatkan jahe, tetapi mereka sudah
mengenal dan memahami bahwa minuman jahe cukup memberikan keuntungan
bagi hidupnya (Santoso, 1994).
1.2 Klasifikasi jahe
Jahe (Zingiber officinale Rosc.) termasuk dalam ordo Zingiberales, famili
Zingiberaceae, dan genus Zingiber (Simpson, 2006). Kedudukan tanaman jahe
dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan adalah sebagai berikut :
Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiospermae
Kelas : Monocotyledonae
: Zingiberales
Ordo
: Zingiberaceae
Famili
: Zingiber
Genus
: Zingiber officinale Rosc. (Rukmana,
Spesies
2000).
1.3 Morofologi Jahe
Tanaman jahe merupakan terna tahunan, berbatang semu dengan tinggi
antara 30 cm - 75 cm. Berdaun sempit memanjang menyerupai pita, dengan
panjang 15 cm – 23 cm, lebar lebih kurang 2,5 cm, tersusun teratur dua baris
berseling. Tanaman jahe hidup merumpun, beranak-pinak, menghasilkan rimpang
dan berbunga. Berdasarkan ukuran dan warna rimpangnya, jahe dapat dibedakan
menjadi 3 jenis, yaitu: jahe besar (jahe gajah) yang ditandai dengan ukuran
rimpang yang besar, berwarna muda atau kuning, berserat halus dan sedikit
beraroma maupun berasa kurang tajam; jahe putih kecil (jahe emprit) yang
ditandai dengan ukuran rimpang yang termasuk kategori sedang, dengan bentuk
agak pipih, berwarna putih, berserat lembut, dan beraroma serta berasa tajam; jahe
merah yang ditandai dengan ukuran rimpang yang kecil, berwarna merah jingga,
berserat kasar, beraroma serta berasa sangat tajam (Rukmana, 2000).
1.4 Kandungan kimia jahe
Jahe banyak mengandung berbagai fitokimia dan fitonutrien. Beberapa zat
yang terkandung dalam jahe adalah minyak atsiri 2-3%, pati 20-60%, oleoresin,
damar, asam organik, asam malat, asam oksalat, gingerin, gingeron, minyak
damar, flavonoid, polifenol, alkaloid, dan musilago. Minyak atsiri jahe
mengandung zingiberol, linaloal, kavikol, dan geraniol. Rimpang jahe kering per
100 gram bagian yang dapat dimakan mengandung 10 gram air, 10-20 gram
protein, 10 gram lemak, 40-60 gram karbohidrat, 2-10 gram serat, dan 6 gram abu.
Rimpang keringnya mengandung 1-2% gingerol (Suranto, 2004).
Kandungan gingerol dipengaruhi oleh umur tanaman dan agroklimat tempat
tumbuh tanaman jahe. Gingerol juga bersifat sebagai antioksidan sehingga jahe
bermanfaat sebagai komponen bioaktif anti penuaan. Komponen bioaktif jahe
dapat berfungsi melindungi lemak atau membran dari oksidasi, menghambat
oksidasi kolesterol, dan meningkatkan kekebalan tubuh (Kurniawati, 2010).
Selain kandungan senyawa gingerol yang bersifat sebagai antioksidan, jahe
juga mempunyai kandungan nutrisi lainnya yang sangat bermanfaat bagi tubuh.
Berikut kandungan nutrisi jahe tiap 28 g dalam Tabel 2.1:
Nutrisi Jahe (tiap 28 g)
Kalori 22
Natrium 4 mg
Karbohidrat 5 gr
Vitamin C 1,4 mg
Vitamin E (alfa tokoferol) 0,1 mg
Niasin 0,2 mg
Folat 3,1 µg
Kolin 8,1 mg
Magnesium 12 mg
Kalium 116 mg
Tembaga 0,1 mg
Mangan 0,1 mg
1.5 Manfaat Tanaman Jahe
Berkaitan dengan unsur kimia yang dikandungnya, jahe dapat dimanfaatkan
dalam berbagai macam industri, antara lain sebagai berikut: industri minuman
(sirup jahe, instan jahe), industri kosmetik (parfum), industri makanan (permen
jahe, awetan jahe, enting-enting jahe), industri obat tradisional atau jamu, industri
bumbu dapur (Prasetyo, 2003).
Selain bermanfaat di dalam industri, hasil penelitian Kikuzaki dan Nakatani
(1993) menyatakan bahwa oleoresin jahe yang mengandung gingerol memiliki
daya antioksidan melebihi α tokoferol, sedangkan hasil penelitian Ahmed et al.,
(2000) menyatakan bahwa jahe memiliki daya antioksidan yang sama dengan
vitamin C.
2. Sirih (Piper betle L.)
2.1 Klasifikasi Tanaman Sirih (Piper betle L.)
Regnum : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Kelas : Dicotyledoneae
Ordo : Piperales
Famili : Piperaceae
Genus : Piper
Spesies : Piper betle L. (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991).
2.2 Nama Lain Sirih (Piper betle L.)
Daun sirih di Indonesia mempunyai nama yang berbeda–beda sesuai dengan
nama daerahnya masing-masing, yaitu si ureuh (Sunda); sedah, suruh Jawa); sirih
(Sampit); ranub (Aceh); cambia (Lampung); base seda (Bali) (Syamsuhidayat dan
Hutapea, 1991).
2.3 Morfologi Tanaman Sirih (Piper betle L.)
Tanaman sirih merupakan tanaman yang tumbuh memanjat, tinggi 5 cm-15
cm. Helaian daun berbentuk bundar telur atau bundar telur lonjong. Pada bagian
pangkal berbentuk jantung atau agak bundar, tulang daun bagian bawah gundul
atau berbulu sangat pendek, tebal berwarna putih, panjang 5-18 cm, lebar 2,5 -
10,5 cm. Daun pelindung berbentuk lingkaran, bundar telur sungsang atau lonjong
panjang kira-kira 1 mm. Perbungaan berupa bulir, sendiri-sendiri di ujung cabang
dan berhadapan dengan daun. Bulir bunga jantan, panjang gaggang 1,5 - 3 cm,
benang sari sangat pendek. Bulir bunga betina, panjang gaggang 2,5 – 6 cm,
kepala putik 3 – 5. Buah Buni, bulat dengan ujung gundul. Bulir masak berbulu
4 kelabu, rapat, tebal 1– 1,5 cm. Biji berbentuk bulat (Syamsuhidayat dan Hutapea,
1991).
2.4 Kandungan Kimia Daun Sirih (Piper betle L.)
Kandungan kimia daun sirih antara lain saponin, flavonoid, polifenol, dan
minyak atsiri (Syamshidayat dan Hutapea, 1991).
2.5 Kegunaan Daun Sirih (Piper betle L.)
Daun Sirih mempunyai khasiat sebagai obat batuk, obat bisul, obat sakit
mata, obat sariawan, obat hidung berdarah (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991)
3. Sereh (Cymbopogon nardus L.)
3.1 Tinjauan Tanaman Serai (Cymbopogon nardus L.)
Serai dipercaya berasal dari Asia Tenggara atau Sri Lanka. Tanaman ini
tumbuh alami di Sri Lanka, tetapi dapat ditanam pada berbagai kondisi tanah di
daerah tropis yang lembab, cukup sinar matahari dan memiliki curah hujan relatif
tinggi. Kebanyakan serai ditanam untuk menghasilkan minyak atsirinya secara
komersial dan untuk pasar lokal sebagai perisa atau rempah ratus (Chooi, 2008).
Tanaman serai banyak ditemukan di daerah jawa yaitu pada dataran rendah yang
memiliki ketinggian 60-140 mdpl (Armando, 2009).
Tanaman serai dikenal dengan nama berbeda di setiap daerah. Daerah
Jawa mengenal serai dengan nama sereh atau sere. Daerah Sumatera dikenal dengan
nama serai, sorai atau sanger-sange. Kalimantan mengenal nama serai dengan nama
belangkak, senggalau atau salai. Nusa Tenggara mengenal serai dengan nama see,
nau sina atau bu muke. Sulawesi mengenal nama serai dengan nama tonti atau sare
sedangkan di Maluku dikenal dengan nama hisa atau isa (Syamsuhidayat dan
Hutapea, 1991).
3.2 Klasifikasi Tanaman Serai (Cymbopogon nardus L.)
Regnum : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Monocotyledonae
Ordo : Poales
Famili : Poaceae/Graminae
Genus : Cymbopogon
Spesies : Cymbopogon nardus L. Rendle
3.3 Morfologi Tanaman Serai (Cymbopogon nardus L.)
Tanaman serai merupakan tanaman dengan habitus terna perenial yang
tergolong suku rumput-rumputan (Tora, 2013). Tanaman serai mampu tumbuh
sampai 1-1,5 m. Panjang daunnya mencapai 70-80 cm dan lebarnya 2-5 cm,
berwarna hijau muda, kasar dan memiliki aroma yang kuat (Wijayakusuma, 2005).
Serai memiliki akar yang besar dan merupakan jenis akar serabut yang berimpang
pendek (Arzani dan Riyanto, 1992). Batang serai bergerombol dan berumbi, serta
lunak dan berongga. Isi batangnya merupakan pelepah umbi pada pucuk dan
berwarna putih kekuningan. Namun ada juga yang berwarna putih keunguan atau
kemerahan (Arifin, 2014).
Daun tanaman serai berwarna hijau dan tidak bertangkai. Daunnya kesat,
panjang, runcing dan memiliki bentuk seperti pita yang makin ke ujung makin
runcing dan berbau citrus ketika daunnya diremas. Daunnya juga memiliki tepi
yang kasar dan tajam. Tulang daun tanaman serai tersusun sejajar dan letaknya
tersebar pada batang. Panjang daunnya sekitar 50-100 cm sedangkan lebarnya kirakira 2 cm.
Daging daun tipis, serta pada permukaan dan bagian bawah daunnya
berbulu halus (Arzani dan Riyanto, 1992).
Tanaman serai jenis ini jarang sekali memiliki bunga. Jika ada, bunganya
tidak memiliki mahkota dan merupakan bunga berbentuk bulir majemuk,
bertangkai atau duduk, berdaun pelindung nyata dan biasanya berwarna putih. Buah
dan bijinya juga jarang sekali atau bahkan tidak memiliki buah maupun biji (Arzani
dan Riyanto, 1992; Sudarsono dkk., 2002).
3.4 Kandungan Tanaman Serai (Cymbopogon nardus L.)
Tanaman serai mengandung minyak esensial atau minyak atsiri. Minyak
atsiri dari daun serai rata-rata 0,7% (sekitar 0,5% pada musim hujan dan dapat
mencapai 1,2% pada musim kemarau). Minyak sulingan serai wangi berwarna
kuning pucat. Bahan aktif utama yang dihasilkan adalah senyawa aldehid
(sitronelol-C10H6O) sebesar 30-45%, senyawa alkohol (sitronelol-C10H20O dan
geraniol-C10H18O) sebesar 55-65% dan senyawa-senyawa lain seperti geraniol,
sitral, nerol, metal, heptonon dan dipentena (Khoirotunnisa, 2008). Senyawa
penyusun minyak atsiri serai dapat dilihat pada Tabel II.1 :
Tabel II.1 Senyawa Penyusun Minyak Atsiri Serai
Senyawa Penyusun Kadar (%)
Sitronelal (antioksidan) 32-45
Geraniol (antioksidan) 12-18
Sitronellol 12-15
Geraniol asetat 3-8
Sitronellil asetat
2-4
L- Limonene
2-5
Elemol & Seskwiterpene
2-5
lain
2-5
Elemene & Cadinene
Sumber : Guenther (2006)
Pada akar tanaman serai mengandung kira-kira 0,52% alkaloid dari 300 g
bahan tanaman. Daun dan akar tanaman serai mengandung flavonoid yaitu luteolin,
luteolin 7-O-glucoside (cynaroside), isoscoparin dan 2''-O-rhamnosyl isoorientin.
Senyawa flavonoid lain yang diisolasi dari bagian aerial tanaman serai yaitu
quercetin, kaempferol dan apigenin (Opeyemi Avoseh, 2015).
3.5 Manfaat Tanaman Serai (Cymbopogon nardus L.)
Berdasarkan pada beberapa penelitian mengenai tanaman serai, ekstrak
daunnya mengandung senyawa senyawa alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, fenol
dan steroid yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan melalui penghambatannya
terhadap radikal bebas DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) dengan nilai IC 50 terbaik
pada ekstrak etanol 70% sebesar 79,444 mg/L (Rahmah, 2014).
Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Agbafor dan Akubugwo (2008),
ekstrak serai dengan dosis 100 mg/KgBB dan 200 mg/KgBB yang diberikan selama
7 hari memiliki efek sebagai hipokolesterolemia. Aktivitas kolesterol ditunjukkan
dengan adanya senyawa flavonoid yang dapat memperbaiki profil lipid secara
bermakna, hal ini terjadi karena flavonoid berperan sebagai antioksidan dan dapat
menekan terbentuknya interleukin proinflamasi. Flavonoid mampu memperbaiki
endotel pembuluh darah, dapat mengurangi kepekaan LDL terhadap pengaruh
radikal bebas (Wayan dan Made, 2012).
Penelitian lainnya menunjukkan bahwa minyak atsiri yang disemprotkan
ke udara membantu menghilangkan bakteri, jamur, bau pengap, dan bau yang tidak
mengenakkan. Selain menyegarkan udara, aroma alami minyak atsiri juga dapat mempengaruhi
emosi dan fikiran serta menciptakan suasana tentram dan harmonis (Arzani dan Riyanto,1992).
Anda mungkin juga menyukai
- Laprak Pembuatan Medium AccDokumen39 halamanLaprak Pembuatan Medium AccNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Acc Laporan Mikro SterilDokumen41 halamanAcc Laporan Mikro SterilNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Materi Persiapan Proposal NureDokumen22 halamanMateri Persiapan Proposal NureNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Tugas KuisoDokumen1 halamanTugas KuisoNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Soal Jawab Spektrofotometer NureDokumen3 halamanSoal Jawab Spektrofotometer NureNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Makalah Anmakmin (Bahan Pengembang) Kelompok 9Dokumen18 halamanMakalah Anmakmin (Bahan Pengembang) Kelompok 9Nur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Kaper MadDokumen1 halamanKaper MadNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Cover SKP Pa MatDokumen1 halamanCover SKP Pa MatNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Vial AmpulDokumen30 halamanVial AmpulNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Bab Ii Tetes Mata-1Dokumen11 halamanBab Ii Tetes Mata-1Nur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Acc Laporan Praktek Kerja Lapangan Puskesmas Dungingi 3 2Dokumen38 halamanAcc Laporan Praktek Kerja Lapangan Puskesmas Dungingi 3 2Nur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Bab 1 Dan 5 MetabolismeDokumen4 halamanBab 1 Dan 5 MetabolismeNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar BelakangDokumen43 halamanBab 1 Pendahuluan 1.1 Latar BelakangNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Surat FaterDokumen2 halamanSurat FaterNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Tugas Kimai Dasar AlkanaDokumen13 halamanTugas Kimai Dasar AlkanaNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- 3 Fix JurnalDokumen9 halaman3 Fix JurnalNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- DispensingDokumen10 halamanDispensingNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- SPEKTRODokumen31 halamanSPEKTRONur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- BB 4 KLTDokumen5 halamanBB 4 KLTNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Partisi Cair-Cair Fito 2 PRINTDokumen46 halamanPartisi Cair-Cair Fito 2 PRINTNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Bab Iv AntidiareDokumen9 halamanBab Iv AntidiareNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- 3rd BAB 3 DiuretikDokumen10 halaman3rd BAB 3 DiuretikNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Lampiran Fartoks 3Dokumen2 halamanLampiran Fartoks 3Nur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- OBAT KUMUR KunciiDokumen2 halamanOBAT KUMUR KunciiNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Wa0007.Dokumen14 halamanWa0007.Nur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Bab Ii-1Dokumen23 halamanBab Ii-1Nur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- Bab 1&5 AnfrDokumen4 halamanBab 1&5 AnfrNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- TP Fartoks DiuretikDokumen3 halamanTP Fartoks DiuretikNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- P2. Bab1 AnfarDokumen3 halamanP2. Bab1 AnfarNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat
- 1st BAB 3 Diuretik FixDokumen4 halaman1st BAB 3 Diuretik FixNur'ain DJ. SilakaBelum ada peringkat