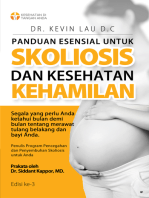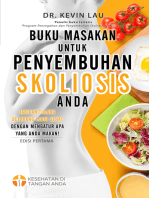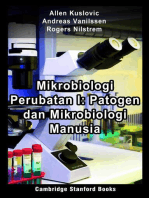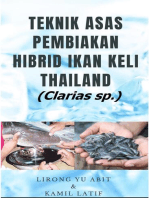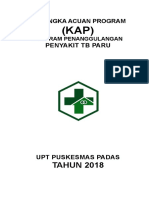Bukupedoman TB
Bukupedoman TB
Diunggah oleh
Hesti Nurmala RizqiHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Bukupedoman TB
Bukupedoman TB
Diunggah oleh
Hesti Nurmala RizqiHak Cipta:
Format Tersedia
Program Penanggulangan Tuberkulosis
DAFTAR KONTRIBUTOR
1. Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 2. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik 3. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 4. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 5. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 6. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) 7. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) 8. Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) 9. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) 10. Perkumpulan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPKMI) 11. Royal Netherlands Tuberculosis Association (KNCV) 12. World Health Organization (WHO) 13. AusAID (Australian Agency for International Development)
Program Penanggulangan Tuberkulosis
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Kontributor Daftar isi Sambutan Menteri Kesehatan RI
i iii vii viii ix x
Sambutan Ketua PB IDI Kata Pengantar Daftar Singkatan
BAB
PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS 1. Pendahuluan 2. Latar Belakang 3. Visi dan Misi 4. Tujuan Penanggulangan Tuberkulosis 5. Kebijakan Operasional 6. Strategi 7. Kegiatan 8. Organisasi Pelaksanaan TUBERKULOSIS 1. Kuman dan Cara Penularannya 2. Riwayat Terjadinya Tuberkulosis 3. Komplikasi pada Penderita TBC 4. Perjalanan Alamiah TBC yang tidak diobati 5. Pengaruh Inkeksi HIV
1 1 2 3 3 4 5 5
BAB
8 9 9 10 10
BAB
DIAGNOSIS PENDERITA TUBERKULOSIS
ii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
1. 2. 3. 4.
Gejala-gejala Tuberkulosis Penemuan Penderita TBC Diagnosis Tuberkulosis Indikasi Pemeriksaan Foto Rontgen Dada
11 11 12 18
BAB
KLASIFIKASI PENYAKIT dan TIPE PENDERITA 1. Tujuan Penentuan Klasifikasi Penyakit dan Tipe Penderita 2. Klasifikasi Penyakit 3. Tipe Penderita
19 19 20
BAB
PEMERIKSAAN DAHAK SECARA MIKROSKOPIS LANGSUNG 1. Tujuan Pemeriksaan Dahak 2. Daftar Tersangka Penderita (Suspek) TBC 3. Pengumpulan Dahak 4. Pemberian Nomor Identitas Sediaan 5. Pembuatan dan Penyimpanan Sediaan Hapus Dahak 6. Permohonan Pemeriksaan dan Pengiriman sediaan Dahak 7. Pewarnaan Sediaan dengan Metode Ziehl Neelsen 8. Pembacaan Sediaan 9. Pencatatan Hasil Pembacaan 10. Penyimpanan Sediaan untuk di Cross Check 11. Pembuangan Limbah Laboratorium 12. Keamanan Kerja di Laboratorium 13. Pemantapan Mutu Laboratorium 14. Pemeliharaan Mikroskop PENGOBATAN PENDERITA 1. Tujuan 2. Jenis dan Dosis OAT 3. Prinsip Pengobatan 4. Paduan OAT di Indonesia 5. Pemantauan Kemajuan Hasil Pengobatan TBC pada Orang Dewasa 6. Hasil Pengobatan dan Tindak Lanjut 7. Tatalaksana Penderita yang tidak berobat teratur 8. Pengawasan Menelan Obat 9. Pengobatan TBC pada Anak 10. Pengobatan Pencegahan untuk Anak 11. Pengobatan Tuberkulosis pada keadaan Khusus 12. Efek samping Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 46 CROSS CHECK SEDIAAN DAHAK 1. Maksud dan Prinsip Pemeriksaan Cross Check
iii
22 22 23 24 24 25 26 27 28 28 28 28 29 30
BAB
31 31 32 32 35 39 40 42 43 44 44
BAB
51
Program Penanggulangan Tuberkulosis
2. Cara Pengambilan Sample Sediaan Untuk di Cross Check 3. Aspek yang dinilai dalam Cross Check 4. Alur Cross Check 5. Cara Menghitung Hasil Cross Check 6. Interpretasi Hasil Cross Check 7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Hasil Cross Check
51 51 52 52 53 53
BAB
PENYULUHAN TUBERKULOSIS 1. Penyuluhan Langsung Perorangan 2. Penyuluhan Kelompok 3. Penyuluhan Massa 4. Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan TBC 5. Advokasi PENCATATAN DAN PELAPORAN 1. Pencatatan di Unit Pelayanan Kesehatan 2. Pencatatan di Laboratorium PRM/RS/BP.4 3. Pencatatan dan Pelaporan di Kabupaten / Kota 4. Pencatatan dan Pelaporan di Propinsi 5. Contoh Formulir Pencatatan Pelaporan yang digunakan 6. Petunjuk cara Pengisian Formulir Pencatatan dan Pelaporan SUPRVISI 1. Tujuan Supervisi 2. Pelaksanaan Supervisi 3. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam Supervisi 4. Pemecahan Masalah Supervisi 5. Laporan Supervisi 6. Contoh Materi Supervisi MONITORING DAN EVALUASI 1. Proporsi Suspek yang Diperiksa Dahaknya 2. Proporsi Penderita BTA Positif Diantara Suspek 3. Proporsi Penderita TBC Paru BTA Positif Diantara Semua Penderita TBC Paru tercatat 4. Angka Konversi (Conversion Rate) 5. Angka Kesembuhan (Cure Rate) 6. Error Rate 7. Case Notification Rate 8. Case Detection Rate
56 58 58 59 59
BAB
60 61 61 61 61 62
BAB
80 80 81 82 82 83
BAB
94 94 95 95 96 97 97 98
iv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
BAB
PERENCANAAN 1. Analisis Situasi 2. Identifikasi dan Menetapkan Masalah Prioritas 3. Menetapkan Tujuan Untuk Mangatasi Masalah 4. Menetapkan Alternatif Pemecahan Masalah 5. Menyusun Rencana Kegiatan dan Penganggaran (PoA) 6. Menyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi PENGELOLAAN LOGISTIK 1. Pengelolaan OAT 2. Pengelolaan Logistik Lainnya
99 100 101 101 102 106
BAB
107 109
BAB
PELATIHAN 1. Sasaran Latih 2. Materi Pelatihan 3. Kegiatan Pelatihan
111 112 112
LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 : Bentuk-bentuk Formulir Isian Lampiran 2 : Uraian Tugas Program TBC Petugas Kabupaten/Kota Uraian Tugas Program TBC Petugas UPK Contoh Analisis Data Hasil Kegiatan di UPK Daftar Kepustakaan
Program Penanggulangan Tuberkulosis
SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan serta ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Program Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai peranan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan penerapan teknologi kesehatan secara tepat oleh petugas-petugas kesehatan yang didukung peran serta aktif masyarakat. Hasil penelitian telah mendorong pesatnya perkembangan Ilmu Kesehatan, baik berupa penemuan obat-obatan, vaksin, maupun perkembangan epidemiologi terapan dan pergerakan peran serta masyarakat. Untuk menyebar luaskan manfaatnya, diperlukan wahana serta sarana yang berdaya guna. Oleh karena itu penyusunan dan penyebar luasan buku-buku pedoman merupakan upaya yang harus dikembangkan dalam rangka pemutakhiran secara berkesinambungan. Buku-buku tersebut diperlukan oleh pelaksana upaya kesehatan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta berguna untuk pembinaan. Buku Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB) ini memuat strategi baru, dimana mulai tahun 2000 secara bertahap semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang baku kepada penderita TB dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Shortcourse) Penyusunan buku ini mendaya gunakan secara terpadu semua program dalam lingkungan Departemen Kesehatan & Kesejahteraan Sosial maupun sektor terkait, PDPI, PAPDI, IDAI, PPTI, WHO dan merupakan suatu bukti dari semangat Gerdunas yang sangat kami hargai. Semoga buku ini dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang berperan serta dalam penanggulangan TB di Indonesia.
Jakarta, April 2000. Menteri Kesehatan R.I.
Dr. Achmad Sujudi, MHA.
DAFTAR SINGKATAN
vi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
AIDS
APBN APBD AP
= Acquired Immune Deficiency Syndrome
= Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara = Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah = Akhir Pengobatan
Bapelkes = Balai Pelatihan Kesehatan
BCG
BLK BLN BUMN BTA BP4
= Bacillus Calmette et Guerin
= Balai Laboratorium Kesehatan = Bantuan Luar Negeri = Badan Usaha Milik Negara = Basil Tahan Asam = Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru
Dati II
Ditjen PPM & PL Ditjen Binkesmas Ditjen Yanmed DIP DOTS
= Daerah Tingkat II
= Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan = Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat = Direktorat Jenderal Pelayanan Medis = Daftar Isian Proyek = Directly Observed Treatment, Shorcourse chemotherapy
vii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
DPS = Prakter Dokter Swasta
E FEFO = Etambutol = First Expired First Out
GERDUNASTB = Gerakan Terpadu Nasional
viii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Penanggulanga n Tuberkulosis
GFK H = Gudang Farmasi Kabupaten/ Kota = Isoniasid (INH = Iso Niacid Hydrazide)
HAKLI = Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
HIV = Human Immunodeficiency Virus
IAKMI
= Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
ix
Program Penanggulangan Tuberkulosis
IBI = Ikatan Bidan Indonesia IDAI = Ikatan Dokter Anak Indonesia
IDAI KPP Ko. = Ikatan Dokter Indonesia = Kelompok Puskesmas Pelaksana = Kota
x
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Kab. = Kabupaten
Lab. LP LSM LPLPO MDR = = = = = Laboratorium Lapang Pandang Lembaga Swadaya Masyarakat Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat Multiple Drugs Resistance (kekebalan ganda terhadap obat)
No. = Nomor
OAT PAPDI = Obat Anti Tuberkulosis = Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia
xi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
PDPI
= Perhimpunan Dokter Paru Indonesia
PLKN = Pusat Latihan Kusta Nasional
POGI POM PPM P2ML = = = = Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Pengawasan Obat dan Makanan Puskesmas Pelaksana Mandiri Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
PPNI = Perhimpunan Perawat
xii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Nasional Indonesia
PPTI PRM PS Puskesmas Pustu Puslabkes = = = = = = Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Puskesmas Rujukan Mikroskopis Puskesmas Satelit Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pembantu Pusat Laboratorium Kesehatan
xiii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
R = Rifampisin RSTP = Rumah Sakit TBC Paru
Reg. S SKRT = Register = Streptomisin = Survei Kesehatan Rumah Tangga
xiv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
SPS = Sewaktu-PagiSewaktu TNA = Training Need Assessment
TB/TBC = Tuberkulosis UPK Wasor WHO Z ZN = = = = = Unit Pelayanan Kesehatan Wakil Supervisor World Health Organization Pirazinamid Ziehl Neelsen
xv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
BAB I PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS 1. PENDAHULUAN
Sejak tahun 1995, program Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis Paru, telah dilaksanakan dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Shortcourse chemotherapy) yang direkomendasi oleh WHO. Kemudian berkembang seiring dengan pembentukan GERDUNAS-TBC, maka Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis Paru berubah menjadi Program Penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Penanggulangan dengan strategi DOTS dapat memberikan angka kesembuhan yang tinggi. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS merupakan strategi kesehatan yang paling cost- effective. Dasar kebijaksanaan: 1. Evaluasi program TBC yang dilaksanakan bersama oleh Indonesia dan WHO pada April 1994. (Indonesia WHO joint evaluation on National TB Program) 2. Lokakarya Nasional Program P2TBC pada September 1994. 3. Dokumen Perencanaan (Plan of action) pada bulan September 1994. 4. Rekomendasi Komite Nasional Penanggulangan TBC Paru (KOMNAS-TBC, 9 September 1996) 5. Gerdunas-TBC (Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, 24 Maret 1999). Dengan strategi DOTS, manajemen penanggulangan TBC di Indonesia, ditekankan pada tingkat kabupaten / kota.
2. LATAR BELAKANG 2.1. Masalah dunia
Mycobacterium tuberculosis telah meng-infeksi sepertiga penduduk dunia Pada tahun 1993, WHO mencanangkan kedaruratan global penyakit TBC, karena pada sebagian besar negara di dunia, penyakit TBC tidak terkendali. Ini disebabkan banyaknya penderita yang tidak berhasil disembuhkan, terutama penderita menular (BTA positif). Pada tahun 1995, diperkirakan setiap tahun terjadi sekitar 9 juta penderita baru TBC dengan kematian 3 juta orang (WHO, Treatment of Tuberculosis, Guidelines for National Programmes, 1997). Di negara-negara berkembang kematian TBC merupakan 25% dari seluruh kematian, yang sebenarnya dapat dicegah. Diperkirakan 95% penderita TBC berada di negara berkembang, 75% penderita TBC adalah kelompok usia produktif (15-50 tahun).
xvi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Munculnya epidemi HIV/AIDS di dunia, diperkirakan penderita TBC akan meningkat. Kematian wanita karena TBC lebih banyak dari pada kematian karena kehamilan, persalinan dan nifas (WHO).
2.2. Masalah Indonesia
Penyakit TBC merupakan masalah utama kesehatan masyarakat: Tahun 1995, hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) menunjukkan bahwa penyakit TBC merupakan penyebab kematian nomor tiga (3) setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernafasan pada semua kelompok usia, dan nomor satu (1) dari golongan penyakit infeksi. Tahun 1999, WHO memperkirakan setiap tahun terjadi 583.000 kasus baru TBC dengan kematian karena TBC sekitar 140.000. Secara kasar diperkirakan setiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 130 penderita baru TBC paru BTA positif. Penyakit TBC menyerang sebagian besar kelompok usia kerja produktif, kelompok ekonomi lemah, dan berpendidikan rendah. Sampai saat ini program Penanggulangan TBC dengan Strategi DOTS belum dapat menjangkau seluruh Puskesmas. Demikian juga Rumah Sakit Pemerintah, swasta dan unit pelayanan kesehatan lainnya. Tahun 1995 - 1998, cakupan penderita TBC dengan strategi DOTS baru mencapai sekitar 10 % dan error rate pemeriksaan laboratorium belum dihitung dengan baik meskipun cure rate lebih besar dari 85%. Penatalaksanaan penderita dan sistim pencatatan pelaporan belum seragam disemua unit pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Pengobatan yang tidak teratur dan kombinasi obat yang tidak lengkap dimasa lalu, diduga telah menimbulkan kekebalan ganda kuman TBC terhadap Obat Anti-Tuberkulosis (OAT) atau Multi Drug Resistance (MDR).
3. VISI dan MISI 3.1. Visi
Tuberkulosis tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat.
3.2. Misi
Menetapkan kebijaksanaan, memberikan panduan serta membuat evaluasi secara tepat, benar dan lengkap. Menciptakan iklim kemitraan dan transparansi pada upaya penanggulangan penyakit TBC. Mempermudah akses pelayanan penderita TBC untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar mutu.
xvii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
4. TUJUAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS 4.1. Jangka Panjang
Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit TBC dengan cara memutuskan rantai penularan, sehingga penyakit TBC tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat Indonesia.
4.2. Jangka Pendek
1) Tercapainya angka kesembuhan minimal 85 % dari semua penderita baru BTA positif yang ditemukan. 2) Tercapainya cakupan penemuan penderita secara bertahap sehingga pada tahun 2005 dapat mencapai 70% dari perkiraan semua penderita baru BTA positif.
5. KEBIJAKAN OPERASIONAL
Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan kebijakan operasional sebagai berikut:
5.1. Penanggulangan TBC di Indonesia dilaksanakan dengan desentralisasi sesuai kebijaksanaan Departemen Kesehatan. 5.2. Penanggulangan TBC dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelayanan Kesehatan (UPK), meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan swasta, BP4 serta Praktek Dokter Swasta (PDS) dengan melibatkan peran serta masyarakat secara paripurna dan terpadu. 5.3. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan penanggulangan TBC, prioritas ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, penggunaan obat yang rasional dan paduan obat yang sesuai dengan strategi DOTS. 5.4. Target program adalah angka konversi pada akhir pengobatan tahap intensif minimal 80%, angka kesembuhan minimal 85% dari kasus baru BTA positif, dengan pemeriksaan sediaan dahak yang benar (angka kesalahan maksimal 5 %). 5.5. Untuk mendapatkan pemeriksaan dahak yang bermutu, maka dilaksanakan pemeriksaan uji silang (Cross check) secara rutin oleh Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) dan laboratorium rujukan yang ditunjuk. 5.6. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk penanggulangan TBC Nasional diberikan kepada penderita secara cuma-cuma dan dijamin ketersediaannya.
i
Program Penanggulangan Tuberkulosis
5.7. Untuk mempertahankan kualitas pelaksanaan program, diperlukan sistem pemantauan, supervisi dan evaluasi program 5.8. Menggalang kerja sama dan kemitraan dengan program terkait, sektor pemerintah dan swasta.
6. STRATEGI.
ii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
6.1. Paradigma Sehat 1) Meningkatkan penyuluhan untuk menemukan kontak sedini mungkin, serta meningkatkan cakupan program. 2) Promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat. 3) Perbaikan perumahan serta peningkatan status gizi, pada kondisi tertentu. 6.2. Strategi DOTS, sesuai rekomendasi WHO, terdiri atas 5 komponen 1) Komitmen politis dari para pengambil keputusan, termasuk dukungan dana. 2) Diagnosis TBC dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis. 3) Pengobatan dengan paduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) jangka pendek dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO). 4) Kesinambungan persediaan OAT jangka pendek dengan mutu terjamin. 5) Pencatatan dan pelaporan secara baku untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan TBC. 6.3. Peningkatan mutu pelayanan. 1) Pelatihan seluruh tenaga pelaksana. 2) Ketepatan diagnosis TBC dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopik. 3) Kualitas laboratorium diawasi melalui pemeriksaan uji silang (cross check). 4) Untuk menjaga kualitas pemeriksaan laboratorium, dibentuklah KPP (Kelompok Puskesmas Pelaksana) terdiri dari 1 (satu) PRM (Puskesmas Rujukan Mikroskopik) dan beberapa PS (Puskesmas Satelit). Untuk daerah dengan geografis sulit dapat dibentuk PPM (Puskesmas Pelaksana Mandiri). 5) Ketersediaan OAT bagi semua penderita TBC yang ditemukan. 6) Pengawasan kualitas OAT dilaksanakan secara berkala dan terus menerus. 7) Keteraturan menelan obat sehari-hari diawasi oleh Pengawas Menelan Obat (PMO). Keteraturan pengobatan tetap merupakan tanggung jawab petugas kesehatan. 8) Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan dengan teratur, lengkap dan benar.
iii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
6.4. Pengembangan program dilakukan secara bertahap ke seluruh UPK. 6.5. Peningkatan kerjasama dengan semua pihak melalui kegiatan advokasi, diseminasi informasi dengan memperhatikan peran masing-masing. 6.6. Kabupaten/kota sebagai titik berat manajemen program meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta mengupayakan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana). 6.7. Kegiatan penelitian dan pengembangan melibatkan semua unsur terkait. 6.8. Memperhatikan komitmen internasional. dilaksanakan dengan
7. KEGIATAN
7.1. Penemuan dan diagnosis penderita. 7.1.1. Penentuan klasifikasi penyakit dan tipe tuberkulosis. 7.1.2. Pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung. 7.1.3. Pengobatan penderita dan pengawasan pengobatan. 7.2. Cross check sediaan dahak 7.3. Pencatatan dan pelaporan. 7.4. Penyuluhan tuberkulosis. 7.5. Supervisi. 7.6. Monitoring dan evaluasi. 7.7. Perencanaan. 7.8. Pengelolaan logistik. 7.9. Pelatihan. 7.10. Penelitian
Uraian kegiatan tersebut diatas akan dibahas dalam bab tersendiri.
8. ORGANISASI PELAKSANAAN 8.1. Tingkat Pusat.
Upaya penanggulangan TBC di tingkat pusat dibawah tanggung jawab dan kendali Direktur Jenderal PPM & PL. Untuk menggalang kemitraan dibentuk Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (GERDUNAS-TBC) yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan R.I. pada tanggal 24 Maret 1999, bertepatan dengan Peringatan hari TBC sedunia. GERDUNAS-TBC merupakan organisasi fungsional yang terdiri dari: Komite Nasional (KOMNAS), Komite Ahli (KOMLI), Tim Teknis yang terdiri dari enam (6) Kelompok Kerja (POKJA).
iv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Menteri Kesehatan dalam menetapkan kebijaksanaan umum, dibantu oleh KOMNAS TBC. Direktur Jenderal PPM & PL dalam menetapkan kebijaksanaan teknis, dibantu oleh KOMLI TBC yang anggotanya terdiri dari para pakar berbagai disiplin ilmu, wakil dari organisasi profesi dan para pejabat terkait. Untuk pelaksanaan sehari-hari, program dibantu oleh TIM TEKNIS, yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur lintas program dan lintas sektor. Tim Teknis mempunyai 6 kelompok kerja (POKJA) yaitu: 1) Mobilisasi Sosial 2) Pelatihan 3) Monitoring & Evaluasi 4) Pendanaan 5) Logistik dan 6) Operasional.
8.2. Tingkat Propinsi
Di tingkat propinsi dibentuk GERDUNAS-TBC Propinsi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Bentuk dan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
8.3. Tingkat Kabupaten / Kota.
Di tingkat kabupaten / kota dibentuk GERDUNAS-TBC kabupaten / kota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Bentuk dan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten / kota.
8.4. Unit Pelayanan Kesehatan.
Dilaksanakan oleh Puskesmas, Rumah Sakit, BP4/Klinik dan Praktek Dokter Swasta.
8.4.1. Puskesmas
Dalam pelaksanaan di Puskesmas, dibentuk kelompok Puskesmas Pelaksana (KPP) yang terdiri dari Puskesmas Rujukan Mikroskopis (PRM), dengan dikelilingi oleh kurang lebih 5 (lima) Puskesmas Satelit (PS), yang secara keseluruhan mencakup wilayah kerja dengan jumlah penduduk 50.000 - 150.000 jiwa. Pada keadaan geografis yang sulit, dapat dibentuk Puskesmas Pelaksana Mandiri (PPM) yang dilengkapi tenaga dan fasilitas pemeriksaan sputum BTA. 8.4.2. Rumah Sakit dan BP4. Rumah sakit dan BP4 dapat melaksanakan semua kegiatan tatalaksana penderita TBC. Dalam hal tertentu, rumah sakit dan BP4 dapat merujuk penderita kembali ke puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggal penderita untuk mendapatkan pengobatan dan pengawasan selanjutnya. Dalam pengelolaan logistik dan pelaporan, rumah sakit dan BP4 berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten / kota.
v
Program Penanggulangan Tuberkulosis
8.4.3. Klinik dan Dokter Praktek Swasta (DPS). Secara umum konsep pelayanan di Klinik dan DPS sama dengan pelaksanaan pada rumah sakit dan BP4. Dalam hal tertentu, klinik dan DPS dapat merujuk penderita dan specimen ke puskesmas, rumah sakit atau BP4. BAB II TUBERKULOSIS
7. KUMAN dan CARA PENULARAN 7.1. Tuberkulosis.
Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC (Mycobacterium tuberculosis). Sebagian besar kuman TBC menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya.
7.2. Kuman Tuberkulosis
Kuman ini berbentuk batang, mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut pula sebagai Basil Tahan Asam (BTA). Kuman TBC cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh kuman ini dapat dormant, tertidur lama selama beberapa tahun.
7.3. Cara Penularan
Sumber penularan adalah penderita TBC BTA positif. Pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet (percikan dahak). Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup kedalam saluran pernafasan. Setelah kuman TBC masuk kedalam tubuh manusia melalui pernafasan, kuman TBC tersebut dapat menyebar dari paru kebagian tubuh lainnya, melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin menular penderita tersebut. Bila hasil pemeriksaan dahak negatip (tidak terlihat kuman), maka penderita tersebut dianggap tidak menular. Kemungkinan seseorang terinfeksi TBC ditentukan oleh konsentrasi droplet dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut.
7.4. Risiko Penularan.
Risiko penularan setiap tahun (Annual Risk of Tuberculosis Infection = ARTI) di Indonesia dianggap cukup tinggi dan bervariasi antara 1-3 %. Pada daerah dengan ARTI sebesar 1%, berarti setiap tahun diantara 1000 penduduk, 10 (sepuluh) orang akan terinfeksi. Sebagian besar dari orang yang terinfeksi tidak akan menjadi
vi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
penderita TBC, hanya sekitar 10% dari yang terinfeksi yang akan menjadi penderita TBC. Dari keterangan tersebut diatas, dapat diperkirakan bahwa pada daerah dengan ARTI 1%, maka diantara 100.000 penduduk rata-rata terjadi 100 (seratus) penderita tuberkulosis setiap tahun, dimana 50 penderita adalah BTA positif. Faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi penderita TBC adalah daya tahan tubuh yang rendah; diantaranya karena gizi buruk atau HIV/AIDS.
8. RIWAYAT TERJADINYA TUBERKULOSIS 8.1. Infeksi Primer
Infeksi primer terjadi saat seseorang terpapar pertama kali dengan kuman TBC. Droplet yang terhirup sangat kecil ukurannya, sehingga dapat melewati sistem pertahanan mukosilier bronkus, dan terus berjalan sehingga sampai di alveolus dan menetap disana. Infeksi dimulai saat kuman TBC berhasil berkembang biak dengan cara pembelahan diri di paru, yang mengakibatkan peradangan di dalam paru. Saluran limfe akan membawa kuman TBC ke kelenjar limfe di sekitar hilus paru, dan ini disebut sebagai kompleks primer. Waktu antara terjadinya infeksi sampai pembentukan kompleks primer adalah sekitar 4-6 minggu. Adanya infeksi dapat dibuktikan dengan terjadinya perubahan reaksi tuberkulin dari negatif menjadi positif. Kelanjutan setelah infeksi primer tergantung dari banyaknya kuman yang masuk dan besarnya respon daya tahan tubuh (imunitas seluler). Pada umumnya reaksi daya tahan tubuh tersebut dapat menghentikan perkembangan kuman TBC. Meskipun demikian, ada beberapa kuman akan menetap sebagai kuman persister atau dormant (tidur). Kadang kadang daya tahan tubuh tidak mampu menghentikan perkembangan kuman, akibatnya dalam beberapa bulan, yang bersangkutan akan menjadi penderita TBC. Masa inkubasi, yaitu waktu yang diperlukan mulai terinfeksi sampai menjadi sakit, diperkirakan sekitar 6 bulan.
8.2. Tuberkulosis Pasca Primer (Post Primary TBC)
Tuberkulosis pasca primer biasanya terjadi setelah beberapa bulan atau tahun sesudah infeksi primer, misalnya karena daya tahan tubuh menurun akibat terinfeksi HIV atau status gizi yang buruk. Ciri khas dari tuberkulosis pasca primer adalah kerusakan paru yang luas dengan terjadinya kavitas atau efusi pleura.
9. KOMPLIKASI PADA PENDERITA TUBERKULOSIS
Komplikasi berikut sering terjadi pada penderita stadium lanjut: vii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
9.1. Hemoptisis berat (perdarahan dari saluran nafas bawah) yang dapat mengakibatkan kematian karena syok hipovolemik atau tersumbatnya jalan nafas. 9.2. Kolaps dari lobus akibat retraksi bronkial. 9.3. Bronkiectasis (pelebaran bronkus setempat) dan fibrosis (pembentukan jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif) pada paru. 9.4. Pneumotorak (adanya udara didalam rongga pleura) spontan: kolaps spontan karena kerusakan jaringan paru. 9.5. Penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persendian, ginjal dan sebagainya. 9.6. Insufisiensi Kardio Pulmoner (Cardio Pulmonary Insufficiency).
Penderita yang mengalami komplikasi berat perlu dirawat inap di rumah sakit. Penderita TBC paru dengan kerusakan jaringan luas yang telah sembuh (BTA Negatif) masih bisa mengalami batuk darah. Keadaan ini seringkali dikelirukan dengan kasus kambuh. Pada kasus seperti ini, pengobatan dengan OAT tidak diperlukan, tapi cukup diberikan pengobatan simtomatis. Bila perdarahan berat, penderita harus dirujuk ke unit spesialistik.
10. PERJALANAN ALAMIAH TBC YANG TIDAK DIOBATI
Tanpa pengobatan, setelah lima tahun, 50% dari penderita TBC akan meninggal, 25% akan sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh tinggi, dan 25% sebagai kasus kronik yang tetap menular (WHO, 1996).
11. PENGARUH INFEKSI HIV
Infeksi HIV mengakibatkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh seluler (Cellular immunity), sehingga jika terjadi infeksi oportunistik, seperti tuberkulosis, maka yang bersangkutan akan menjadi sakit parah bahkan bisa mengakibatkan kematian. Bila jumlah orang terinfeksi HIV meningkat, maka jumlah penderita TBC akan meningkat, dengan demikian penularan TBC di masyarakat akan meningkat pula.
viii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
BAB III DIAGNOSIS PENDERITA TUBERKULOSIS
12. GEJALA-GEJALA TUBERKULOSIS 12.1. Gejala utama. Batuk terus menerus dan berdahak selama 3 (tiga) minggu atau lebih. Gejala tambahan, yang sering dijumpai:
Dahak bercampur darah. Batuk darah Sesak nafas dan rasa nyeri dada. Badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa kurang enak badan (malaise), berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan, demam meriang lebih dari sebulan.
12.2.
Gejala-gejala tersebut diatas dijumpai pula pada penyakit paru selain tuberkulosis. Oleh sebab itu setiap orang yang datang ke UPK dengan gejala tersebut diatas, harus dianggap sebagai seorang suspek tuberkulosis atau tersangka penderita TBC, dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung.
13. PENEMUAN PENDERITA TUBERKULOSIS (TBC) 13.1. Penemuan penderita tuberkulosis pada orang dewasa.
Penemuan penderita TBC dilakukan secara pasif, artinya penjaringan tersangka penderita dilaksanakan pada mereka yang datang berkunjung ke unit pelayanan kesehatan. Penemuan secara pasif tersebut didukung dengan penyuluhan secara aktif, baik oleh petugas kesehatan maupun masyarakat, untuk meningkatkan cakupan penemuan tersangka penderita. Cara ini biasa dikenal dengan sebutan passive promotive case finding (penemuan penderita secara pasif dengan promosi yang aktif). Selain itu, semua kontak penderita TBC Paru BTA positif dengan gejala sama, harus diperiksa dahaknya.
Seorang petugas kesehatan diharapkan menemukan tersangka penderita sedini mungkin, mengingat tuberkulosis adalah penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian.
Semua tersangka penderita harus diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 2 hari berturut-turut, yaitu sewaktu - pagi - sewaktu (SPS). Lihat Bab V butir 3.1.
ix
Program Penanggulangan Tuberkulosis
13.2.
Penemuan penderita tuberkulosis pada anak.
Penemuan penderita tuberkulosis pada anak merupakan hal yang sulit. Sebagian besar diagnosis tuberkulosis anak didasarkan atas gambaran klinis, gambaran radiologis dan uji tuberkulin.
14. DIAGNOSIS TUBERKULOSIS (TBC) 14.1. Diagnosis Tuberkulosis Pada Orang Dewasa
Diagnosis TBC Paru pada orang dewasa dapat ditegakkan dengan ditemukannya BTA pada pemeriksaan dahak secara mikroskopis. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif apabila sedikitnya dua dari tiga spesimen SPS BTA hasilnya positif. Bila hanya 1 spesimen yang positif perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut yaitu foto rntgen dada atau pemeriksaan dahak SPS diulang. - Kalau hasil rntgen mendukung TBC, maka penderita didiagnosis sebagai penderita TBC BTA positif. - Kalau hasil rntgen tidak mendukung TBC, maka pemeriksaan dahak SPS diulangi. Apabila fasilitas memungkinkan, maka dapat dilakukan pemeriksaan lain, misalnya biakan. Bila ketiga spesimen dahak hasilnya negatif, diberikan antibiotik spektrum luas (misalnya Kotrimoksasol atau Amoksisilin) selama 1 2 minggu. Bila tidak ada perubahan, namun gejala klinis tetap mencurigakan TBC, ulangi pemeriksaan dahak SPS. Kalau hasil SPS positif, didiagnosis sebagai penderita TBC BTA positif Kalau hasil SPS tetap negatif, lakukan pemeriksaan foto rntgen dada, untuk mendukung diagnosis TBC. - Bila hasil rntgen mendukung TBC, didiagnosis sebagai penderita TBC BTA negatif Rontgen positif. - Bila hasil rntgen tidak mendukung TBC, penderita tersebut bukan TBC. UPK yang tidak memiliki fasilitas rntgen, penderita dapat dirujuk untuk foto rntgen dada. Lebih jelas lihat alur diagnosis TBC pada orang dewasa di halaman berikut. Di Indonesia, pada saat ini, uji tuberkulin tidak mempunyai arti dalam menentukan diagnosis TBC pada orang dewasa, sebab sebagian besar masyarakat sudah terinfeksi dengan Mycobacterium tuberculosis karena tingginya prevalensi TBC. Suatu uji tuberkulin positif hanya menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah terpapar dengan Mycobacterium tuberculosis. Dilain pihak, hasil uji tuberkulin dapat negatif meskipun orang tersebut menderita tuberkulosis, misalnya pada penderita HIV / AIDS, malnutrisi berat, TBC milier dan morbili.
Bagan-1 ALUR DIAGNOSIS TUBERKULOSIS PARU PADA ORANG DEWASA
Tersangka Penderita TBC (Suspek TBC)
Periksa dahak Sewaktu, Pagi, Sewaktu (SPS)
Hasil BTA
+++ ++ -
x Hasil BTA + - -
Hasil BTA
- - -
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Periksa Rntgen Dada
Beri Antibiotik Spektrum Luas
Hasil Mendukung TBC
Hasil Tidak Mendukung TBC
Tidak ada perbaikan
Ada perbaikan
Ulangi periksa dahak SPS
Penderita TBC
BTA Positif
Hasil BTA +++ ++ + - -
Hasil BTA - - -
Periksa rntgen dada
Hasil mendukung TBC
Hasil Rntgen Neg
TBC BTA Neg
Rntgen Pos
Bukan TBC,
Penyakit Lain
14.2.
Diagnosis Tuberkulosis Pada Anak.
Diagnosis paling tepat adalah dengan ditemukannya kuman TBC dari bahan yang diambil dari penderita, misalnya dahak, bilasan lambung, biopsi dll. Tetapi pada anak hal ini sulit dan jarang didapat, sehingga sebagian besar diagnosis TBC anak didasarkan atas gambaran klinis, gambaran foto rntgen dada dan uji tuberkulin. Untuk itu penting memikirkan adanya TBC pada anak kalau terdapat tanda-tanda yang mencurigakan atau gejala gejala seperti dibawah ini: 1) Seorang anak harus dicurigai menderita tuberkulosis kalau: mempunyai sejarah kontak erat (serumah) dengan penderita TBC BTA positif, terdapat reaksi kemerahan cepat setelah penyuntikan BCG (dalam 3-7 hari), terdapat gejala umum TBC. 2) Gejala umum TBC pada anak: Berat badan turun selama 3 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas dan tidak naik dalam 1 bulan meskipun sudah dengan penanganan gizi yang baik (failure to thrive). Nafsu makan tidak ada (anorexia) dengan gagal tumbuh dan berat badan tidak naik (failure to thrive) dengan adekuat. xi
Program Penanggulangan Tuberkulosis Demam lama/berulang tanpa sebab yang jelas (bukan tifus, malaria atau infeksi saluran nafas akut), dapat disertai keringat malam. Pembesaran kelenjar limfe superfisialis yang tidak sakit, biasanya multipel, paling sering didaerah leher, ketiak dan lipatan paha (inguinal). Gejala-gejala dari saluran nafas, misalnya batuk lama lebih dari 30 hari (setelah disingkirkan sebab lain dari batuk), tanda cairan didada dan nyeri dada. Gejala-gejala dari saluran cerna, misalnya diare berulang yang tidak sembuh dengan pengobatan diare, benjolan (massa) di abdomen, dan tanda-tanda cairan dalam abdomen.
3) Gejala spesifik Gejala-gejala ini biasanya tergantung pada bagian tubuh mana yang terserang, misalnya: TBC kulit/skrofuloderma TBC tulang dan sendi: - tulang punggung (spondilitis): gibbus - tulang panggul (koksitis): pincang, pembengkakan di pinggul - tulang lutut: pincang dan/atau bengkak - tulang kaki dan tangan TBC otak dan saraf: - Meningitis: dengan gejala iritabel, kaku kuduk, muntah-muntah dan kesadaran menurun. Gejala mata: - conjunctivitis phlyctenularis - tuberkel koroid (hanya terlihat dengan funduskopi) Lain-lain. 4) Uji tuberkulin (Mantoux) Uji tuberkulin dilakukan dengan cara Mantoux (penyuntikan intra kutan) dengan semprit tuberkulin 1 cc jarum nomor 26. Tuberkulin yang dipakai adalah tuberkulin PPD RT 23 kekuatan 2 TU. Pembacaan dilakukan 48-72 jam setelah penyuntikan. Diukur diameter transveral dari indurasi yang terjadi. Ukuran dinyatakan dalam milimeter. Uji tuberkulin positif bila indurasi > 10 mm (pada gizi baik), atau > 5 mm pada gizi buruk. Bila uji tuberkulin positif, menunjukkan adanya infeksi TBC dan kemungkinan ada TBC aktif pada anak. Namun, uji tuberkulin dapat negatif pada anak TBC berat dengan anergi (malnutrisi, penyakit sangat berat, pemberian imunosupresif, dll). Jika uji tuberkulin meragukan dilakukan uji ulang. 5) Reaksi cepat BCG Bila dalam penyuntikan BCG terjadi reaksi cepat (dalam 3-7 hari) berupa kemerahan dan indurasi > 5 mm, maka anak tersebut dicurigai telah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. 6) Foto rntgen dada Gambaran rntgen TBC paru pada anak tidak khas dan interpretasi foto biasanya sulit, harus hati-hati, kemungkinan bisa overdiagnosis atau underdiagnosis. Paling mungkin kalau ditemukan infiltrat dengan pembesaran kelenjar hilus atau kelenjar paratrakeal. Gejala lain dari foto rntgen yang mencurigai TBC adalah: - Milier - Atelektasis/kolaps konsolidasi - Infiltrat dengan pembesaran kelenjar hilus atau paratrakeal - Konsolidasi (lobus) - Reaksi pleura dan atau efusi pleura - Kalsifikasi - Bronkiektasis - Kavitas - Destroyed lung. Bila ada diskongruensi antara gambaran klinis dan gambaran rntgen, harus dicurigai TBC. xii
Program Penanggulangan Tuberkulosis Foto rntgen dada sebaiknya dilakukan PA (Postero-Anterior) dan lateral, tetapi kalau tidak mungkin PA saja. 7) Pemeriksaan mikrobiologi dan serologi Pemeriksaan BTA secara mikroskopis langsung pada anak biasanya dilakukan dari bilasan lambung karena dahak sulit didapat pada anak. Pemeriksaan BTA secara biakan (kultur) memerlukan waktu yang lama. Cara baru untuk mendeteksi kuman TBC dengan cara PCR (Polymery Chain Reaction) atau Bactec masih belum dapat dipakai dalam klinis praktis. Demikian juga pemeriksaan serologis seperti ELISA, PAP, Mycodot dan lain-lain, masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk pemakaian dalam klinis praktis. 8) Respons terhadap pengobatan dengan OAT Kalau dalam 2 bulan menggunakan OAT terdapat perbaikan klinis, akan menunjang atau memperkuat diagnosis TBC. Bila dijumpai 3 atau lebih dari hal-hal yang mencurigakan atau gejala-gejala klinis umum tersebut diatas, maka anak tersebut harus dianggap TBC dan diberikan pengobatan dengan OAT sambil di observasi selama 2 bulan. Bila menunjukan perbaikan, maka diagnosis TBC dapat dipastikan dan OAT diteruskan sampai penderita tersebut sembuh. Bila dalam observasi dengan pemberian OAT selama 2 bulan tersebut diatas, keadaan anak memburuk atau tetap, maka anak tersebut bukan TBC atau mungkin TBC tapi kekebalan obat ganda atau Multiple Drug Resistent (MDR). Anak yang tersangka MDR perlu dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapat penatalaksanaan spesialistik. Lebih jelas, lihat Alur Deteksi Dini dan Rujukan TBC Anak pada halaman berikut. Penting diperhatikan bahwa bila pada anak dijumpai gejala-gejala berupa kejang, kesadaran menurun, kaku kuduk, benjolan dipunggung, maka ini merupakan tanda-tanda bahaya. Anak tersebut harus segera dirujuk ke Rumah Sakit untuk penatalaksanaan selanjutnya. Penjaringan Tersangka Penderita TBC Anak bisa berasal dari keluarga penderita BTA positif (kontak serumah), masyarakat (kunjungan Posyandu), atau dari penderita-penderita yang berkunjung ke Puskesmas maupun yang langsung ke Rumah Sakit.
xiii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Bagan 2 ALUR DETEKSI DINI dan RUJUKAN TBC ANAK
Hal-hal yang mencurigakan TBC : 1. Mempunyai sejarah kontak erat dengan penderita TBC yang BTA positif 2. Terdapat reaksi kemerahan lebih cepat (dalam 3-7 hari) setelah imunisasi dengan BCG. 3. Berat badan turun tanpa sebab jelas atau tidak naik dalam 1 bulan meskipun sudah dengan penanganan gizi yang baik (failure to thrive). 4. Sakit dan demam lama atau berulang, tanpa sebab yang jelas. 5. Batuk-batuk lebih dari 3 minggu. 6. Pembesaran kelenjar limfe superfisialis yang spesifik. 7. Skrofuloderma. 8. Konjungtivitis fliktenularis. 9. Tes tuberkulin yang positif (>10 mm). 10. Gambaran foto rontgen sugestif TBC.
BILA > 3 POSITIF
Dianggap TBC
Beri OAT Observasi 2 bulan
Membaik
MEMBURUK/TETAP
TBC
OAT diteruskan
BUKAN TBC
TBC Kebal Obat (MDR)
RUJUK ke RS
PERHATIAN:
Bila terdapat tanda-tanda bahaya seperti Kejang Kesadaran menurun Kaku kuduk Benjolan dipunggung Dan kegawatan lain Segera rujuk ke Rumah Sakit.
Pemeriksaan lanjutan di RS: - Gejala klinis - Uji tuberkulin - Foto rontgen paru - Pemeriksaan mikrobilogi dan serologi - Pemeriksaan patologi anatomi
Prosedur diagnostik dan tatalaksana sesuai dengan prosedur Konsensus Nasional TBC-Anak - IDAI di RS b k t
xiv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
14.3. Diagnosis Tuberkulosis Ekstra Paru Gejala tuberkulosis Ekstra Paru tergantung organ yang terkena, misalnya nyeri dada terdapat pada tuberkulosis pleura (Pleuritis), pembesaran kelenjar limfe superfisialis pada Lymphadenitis TBC dan pembengkakan tulang belakang pada Spondilitis TBC. Diagnosis pasti sulit ditegakkan sedangkan diagnosis kerja dapat ditegakkan dengan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain. Ketepatan diagnosis tergantung ketersediaan alat-alat diagnostik, misalnya peralatan rontgen, biopsi, sarana pemeriksaan patologi anatomi. Seorang penderita TBC Ekstra Paru kemungkinan besar juga menderita TBC Paru, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan dahak dan foto rntgen dada. Pemeriksaan ini penting untuk penentuan paduan obat yang tepat.
15. INDIKASI PEMERIKSAAN FOTO RNTGEN DADA
Umumnya diagnosis TBC Paru ditegakkan dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis, namun pada kondisi tertentu perlu dilakukan pemeriksaan rntgen.
15.1.
Suspek dengan BTA Negatif
Setelah diberikan antibiotik spektrum luas tanpa ada perubahan, periksa ulang dahak SPS. Bila hasilnya tetap negatif, lakukan pemeriksaan foto rntgen dada.
15.2.
Penderita dengan BTA Positif
Hanya pada sebagian kecil dari penderita dengan hasil pemeriksaan BTA Positif, yang perlu dilakukan pemeriksaan foto rntgen dada yaitu: 1) Penderita tersebut diduga mengalami komplikasi, misalnya sesak nafas berat yang memerlukan penanganan khusus contoh: pneumotorak (adanya uadara didalam rongga pleura), pleuritis eksudativa. 2) Penderita yang sering hemoptisis berat, untuk menyingkirkan kemungkinan bronkiektasis (pelebaran bronkus setempat). 3) Hanya 1 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif. Pada kasus ini pemeriksaan foto rntgen dada diperlukan untuk mendukung diagnosis TBC paru BTA positif. Catatan :
Tidak ada gambaran foto rntgen dada yang khas untuk TBC Paru. Beberapa gambaran yang patut dicurigai sebagai proses spesifik adalah infiltrat, kavitas, kalsifikasi dan fibrosis (pembentukan jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif) dengan lokasi dilapangan atas paru (apeks). Gambaran non-spesifik yang ditemukan pada foto rntgen dada pada seorang penderita yang diduga infeksi paru lain dan tidak menunjukkan perbaikan pada pengobatan dengan antibiotik, ada kemungkinan penyebabnya adalah TBC.
xv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
BAB IV KLASIFIKASI PENYAKIT dan TIPE PENDERITA
Penentuan klasifikasi penyakit dan tipe penderita tuberkulosis memerlukan suatu definisi kasus yang memberikan batasan baku setiap klasifikasi dan tipe penderita.
Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan definisi-kasus, yaitu:
Organ tubuh yang sakit: paru atau ekstra paru;
Hasil pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung: BTA positif atau BTA negatif; Riwayat pengobatan sebelumnya: baru atau sudah pernah diobati; Tingkat keparahan penyakit: ringan atau berat.
16. TUJUAN PENENTUAN PENDERITA
KLASIFIKASI
PENYAKIT
DAN
TIPE
Penentuan klasifikasi penyakit dan tipe penderita penting dilakukan untuk menetapkan paduan OAT yang sesuai dan dilakukan sebelum pengobatan dimulai.
17. KLASIFIKASI PENYAKIT 17.1. Tuberkulosis Paru
Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan paru, tidak termasuk pleura (selaput paru).
Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak, TBC Paru dibagi dalam:
1) Tuberkulosis Paru BTA Positif.
Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif. 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto rontgen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif.
2) Tuberkulosis Paru BTA Negatif
Pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif dan foto rontgen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. TBC Paru BTA Negatif Rontgen Positif dibagi berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya, yaitu bentuk berat dan ringan. Bentuk berat bila gambaran foto rntgen dada memperlihatkan gambaran kerusakan paru yang luas (misalnya proses far advanced atau millier), dan/atau keadaan umum penderita buruk.
17.2.
Tuberkulosis Ekstra Paru.
Tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya pleura, selaput otak, selaput jantung (pericardium), kelenjar lymfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain.
TBC ekstra-paru dibagi berdasarkan pada tingkat keparahan penyakitnya, yaitu:
xvi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
1) TBC Ekstra Paru Ringan
Misalnya: TBC kelenjar limphe, pleuritis eksudativa unilateral, tulang (kecuali tulang belakang), sendi, dan kelenjar adrenal. 2) TBC Ekstra-Paru Berat
Misalnya: meningitis, millier, perikarditis, peritonitis, pleuritis eksudativa duplex, TBC tulang belakang, TBC usus, TBC saluran kencing dan alat kelamin. Catatan: Yang dimaksud dengan TBC paru adalah TBC dari parenchyma paru. Sebab itu, TBC pada pleura atau TBC pada kelenjar hilus tanpa ada kelainan radiologis paru, dianggap sebagai penderita TBC ekstra paru. Bila seorang penderita TBC paru juga mempunyai TBC ekstra paru, maka untuk kepentingan pencatatan, penderita tersebut harus dicatat sebagai penderita TBC paru. Bila seorang penderita ekstra paru pada beberapa organ, maka dicatat sebagai TBC ekstra paru pada organ yang penyakitnya paling berat.
18. TIPE PENDERITA
Tipe penderita ditentukan berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya. Ada beberapa tipe penderita yaitu:
18.1.
Kasus Baru
Adalah penderita yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis harian).
18.2.
Kambuh (Relaps)
Adalah penderita tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh, kemudian kembali lagi berobat dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif.
18.3.
Pindahan (Transfer In)
Adalah penderita yang sedang mendapat pengobatan di suatu kabupaten lain dan kemudian pindah berobat ke kabupaten ini. Penderita pindahan tersebut harus membawa surat rujukan/pindah (Form TB.09).
18.4.
Setelah Lalai (Pengobatan setelah default/drop-out )
Adalah penderita yang sudah berobat paling kurang 1 bulan, dan berhenti 2 bulan atau lebih, kemudian datang kembali berobat. Umumnya penderita tersebut kembali dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif.
18.5. Lain-lain 1) Gagal
Adalah penderita BTA positif yang masih tetap positif atau kembali menjadi positif pada akhir bulan ke 5 (satu bulan sebelum akhir pengobatan) atau lebih. Adalah penderita dengan hasil BTA negatif Rntgen positif menjadi BTA positif pada akhir bulan ke 2 pengobatan. xvii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
2) Kasus Kronis.
Adalah penderita dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulang kategori 2.
BAB V PEMERIKSAAN DAHAK SECARA MIKROSKOPIS LANGSUNG
Dalam program penanggulangan TBC, diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung. Diagnosis pasti TBC melalui pemeriksaan kultur atau biakan dahak. Namun, pemeriksaan kultur memerlukan waktu lebih lama (paling cepat sekitar 6 minggu) dan mahal. Pemeriksaan 3 spesimen (SPS) dahak secara mikroskopis langsung nilainya identik dengan pemeriksaan dahak secara kultur atau biakan. Pemeriksaan dahak secara mikroskopis merupakan pemeriksaan yang paling efisien, mudah dan murah, dan hampir semua unit laboratorium dapat melaksanakan. Pemeriksaan dahak secara mikroskopis bersifat spesifik dan cukup sensitif. Mycobacterium tuberculosis sebagai penyebab TBC, berbentuk batang dan mempunyai sifat tahan terhadap penghilangan warna dengan asam dan alkohol. Karena itu disebut Basil Tahan Asam (BTA). Kuman baru dapat dilihat dibawah mikroskop bila jumlahnya paling sedikit 5.000 kuman dalam satu mili-liter dahak. Dahak yang baik untuk diperiksa adalah dahak kental dan purulen (mucopurulent) berwarna hijau kekuning-kuningan, dengan volume 3-5 ml tiap pengambilan.
19. TUJUAN PEMERIKSAAN DAHAK Tujuan pemeriksaan dahak : 19.1. Menegakkan diagnosis dan menentukan klasifikasi/tipe. 19.2. Menilai kemajuan pengobatan. 19.3. Menentukan tingkat penularan. 20. DAFTAR TERSANGKA PENDERITA (SUSPEK) TBC Suspek yang diambil dahaknya harus dicatat pada Formulir TB.06.
xviii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
20.1. Yang harus dicatat dalam formulir TB.06, adalah: 1) Nomor urut 2) Nomor identitas sediaan dahak 3) Nama tersangka penderita 4) Umur dan jenis kelamin 5) Alamat lengkap 6) Tanggal dan hasil pemeriksaan dahak 7) Nomor registrasi laboratorium 2.2 Pencatatan dalam TB.06 mempunyai tujuan : 1) Mengetahui jumlah suspek yang diperiksa. 2) Mengetahui proporsi penderita BTA Positif diantara suspek yang diperiksa 3) Memudahkan pelacakan bila hasil pemeriksaan dahak positif dan penderita tersebut tidak kembali.
21. PENGUMPULAN DAHAK Spesimen dahak dikumpulkan / ditampung dalam pot dahak yang bermulut lebar, berpenampang 6 cm atau lebih dengan tutup berulir, tidak mudah pecah dan tidak bocor. Pot ini harus selalu tersedia di UPK. Diagnosis tuberkulosis ditegakkan dengan pemeriksaan 3 spesimen dahak Sewaktu Pagi Sewaktu (SPS). Spesimen dahak sebaiknya dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan. 21.1. Pelaksanaan pengumpulan dahak SPS. S (sewaktu): dahak dikumpulkan pada saat suspek TBC datang berkunjung pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa sebuah pot dahak untuk mengumpulkan dahak hari kedua. P (Pagi): dahak dikumpulkan dirumah pada pagi hari kedua, segera setelah bangun tidur. Pot dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas di UPK. S (sewaktu): dahak dikumpulkan di UPK pada hari kedua, saat menyerahkan dahak pagi. Untuk menghindari risiko penularan, pengambilan dahak dilakukan ditempat terbuka dan jauh dari orang lain, misalnya di belakang puskesmas. Jika keadaan tidak memungkinkan, gunakanlah kamar terpisah yang mempunyai ventilasi cukup.
xix
Program Penanggulangan Tuberkulosis
21.2. Untuk memperoleh kualitas dahak yang baik, petugas laboratorium harus memperhatikan hal-hal tersebut dibawah ini: 1) Memberi penjelasan mengenai pentingnya pemeriksaan dahak, baik pemeriksaan dahak pertama maupun pemeriksaan dahak ulang. 2) Memberi penjelasan tentang cara batuk yang benar untuk mendapatkan dahak yang kental dan purulen. 3) Memeriksa kekentalan, warna dan volume dahak. Dahak yang baik untuk pemeriksaan adalah berwarna kuning kehijau-hijauan (mukopurulen), kental, dengan volume 3-5 ml. Bila volumenya kurang, petugas harus meminta agar penderita batuk lagi sampai volumenya mencukupi. 4) Jika tidak ada dahak yang keluar, pot dahak dianggap sudah terpakai dan harus dimusnakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kontaminasi kuman TBC. 21.3. Bila seseorang sulit mengeluarkan dahak, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Di rumah: Malam hari sebelum tidur, minum satu gelas teh manis atau menelan tablet gliseril guayakolat 200 mg. 2) Di UPK: Melakukan olah raga ringan (lari-lari kecil) kemudian menarik nafas dalam, beberapa kali. Bila terasa akan batuk, nafas ditahan selama mungkin lalu disuruh batuk. 21.4. Cara Pengumpulan Dahak Pengumpulan dahak dilakukan dengan urutan sebagai berikut: 1) Beri label pada dinding pot yang memuat nomor identitas sediaan dahak (TB.06). 2) Buka pot dahak, pegang tutupnya dan berikan pot itu kepada suspek. 3) Berdiri dibelakang suspek, minta dia memegang pot itu dekat ke bibirnya dan membatukkan dahak kedalam pot. 4) Tutup pot dengan erat. 5) Petugas harus cuci tangan dengan sabun dan air. 22. PEMBERIAN NOMOR IDENTITAS SEDIAAN
xx
Program Penanggulangan Tuberkulosis
22.1. Kaca sediaan dipegang pada kedua sisinya untuk menghindari sidik jari pada badan kaca sediaan. 22.2. Setiap kaca sediaan diberi nomor identitas sediaan sesuai dengan identitas pada pot dahak dengan menggunakan spidol permanent atau pinsil kaca. 22.3. Pemberian nomor identitas sediaan bertujuan untuk mencegah kemungkinan tertukarnya sediaan, baik yang berasal dari UPK itu sendiri maupun dari UPK lain. 22.4. Nomor identitas sediaan terdiri dari 3 kelompok angka dan 1 huruf, sebagai berikut: 1) Kelompok angka pertama terdiri dari 2 angka, misalnya 02, yang merupakan nomor urut kabupaten / kota. 2) Kelompok angka kedua juga terdiri dari 2 angka, misalnya 15, yang merupakan nomor urut UPK. 3) Kelompok angka ketiga terdiri dari 3 angka, misalnya 237, yang merupakan nomor urut sediaan. Nomor urut sediaan dimulai dengan nomor 001 setiap awal tahun. 4) Huruf A atau B atau C, A menunjukan dahak sewaktu pertama, B untuk dahak pagi dan C untuk dahak sewaktu kedua. Contoh nomor identitas sediaan : 02/15/237 A, 02/15/237 B dan 02/15/237 C. 23. PEMBUATAN DAN PENYIMPANAN SEDIAAN HAPUS DAHAK 23.1. Ambil pot dahak dan kaca sediaan yang beridentitas sama dengan pot dahak. 23.2. Buka pot dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya droplet (percikan dahak). 23.3. Buat sediaan hapus dengan ose (sengkelit), dengan urutan sbb: 1) Panaskan ose diatas nyala api spiritus sampai merah dan biarkan sampai dingin. 2) Ambil sedikit dahak dari bagian yang kental dan kuning ke hijau-hijauan (purulen) menggunakan ose yang telah disterilkan diatas. 3) Oleskan dahak secara merata (jangan terlalu tebal tapi jangan terlalu tipis) pada permukaan kaca sediaan dengan ukuran 2 x 3 cm. 4) Masukkan ose kedalam botol (berukuran 300-500 cc) yang berisi pasir dan alkohol 70% (setinggi 3-5 cm diatas pasir), kemudian digoyang-goyang-kan untuk melepaskan partikel yang melekat pada ose / sengkelit. 5) Setelah itu dekatkan ose tersebut pada api spiritus sampai kering, kemudian dibakar pada api spiritus tersebut sampai membara. 6) Keringkan sediaan di udara terbuka, jangan terkena sinar matahari langsung atau diatas api, biasanya memerlukan waktu sekitar 15-30 menit, sebelum sediaan hapus tersebut di fiksasi. 7) Gunakan pinset untuk mengambil sediaan yang sudah kering pada sisi yang berlabel dengan hapusan dahak menghadap keatas. 8) Lewatkan di atas lampu spiritus sebanyak 3 kali (memerlukan waktu sekitar 3-5 detik) untuk fiksasi (kalau terlalu lama dapat merubah bentuk kuman dan membuat sediaan pecah).
xxi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
23.4. Semua sediaan yang sudah difiksasi segera disimpan kedalam kotak sediaan untuk menghindari risiko pecah atau dimakan serangga. 24. PERMOHONAN PEMERIKSAAN DAN PENGIRIMAN SEDIAAN DAHAK Sediaan dahak yang sudah difiksasi disimpan dalam kotak sediaan dan dikirim ke PRM atau laboratorium pembaca lainnya. Pengiriman dilakukan paling lambat satu minggu sekali dengan disertai formulir permohonan laboratorium TBC untuk pemeriksaan dahak (TB.05). Formulir ini harus diisi lengkap. Sebelum pengiriman, petugas harus meneliti kembali isi setiap kotak sediaan: Pastikan setiap sediaan dahak yang akan dikirim disertai formulir TB.05 yang sudah diisi lengkap. Nomor identitas setiap sediaan harus cocok dengan nomor yang ada di dalam formulir. Petugas di PRM atau di laboratorium pembaca lainnya, pada waktu menerima spesimen dari PS atau dari UPK lain yang meminta pemeriksaan, harus meneliti kembali kesamaan nomor pada formulir permohonan laboratorium TBC untuk pemeriksaan dahak (Form TB.05) dengan nomor yang ada pada sediaan. Hasil pemeriksaan / bacaan sediaan diisi oleh petugas yang membaca sediaan tersebut dan ditulis pada bagian bawah formulir ini dan dikirim kembali kepada pemohon. Sebelum dikirim ke pemohon petugas laboratorium harus menulis nomor register laboratorium (akan dijelaskan dalam pencatatan hasil pemeriksaan pada BAB IX hal. 78). Hasil pemeriksaan/bacaan dilaporkan dengan menulis Positif atau Negatif dan memberi tanda rumput ( ) pada kotak yang sesuai dengan tingkat/gradasi positif.
xxii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
25. PEWARNAAN SEDIAAN DENGAN METODE ZIEHL NEELSEN 25.1. Bahan-bahan yang diperlukan : 1) Botol gelas berwarna coklat berisi larutan Carbol Fuchsin 0,3% 2) Botol gelas berwarna coklat berisi asam alkohol (HCl-Alkohol 3%) 3) Botol gelas berwarna coklat berisi larutan Methylene Blue 0,3% 4) Rak untuk pengecatan slide (yang dapat digunakan untuk 12 slide atau lebih) 5) Baskom untuk ditempatkan dibawah rak 6) Corong dengan kertas filter 7) Pipet 8) Pinset 9) Pengukur waktu (timer) 10) Lampu spiritus 11) Air yang mengalir berupa air ledeng atau botol berpipet berisi air. 12) Beberapa rak cadangan Pewarnaan sediaan yang telah difiksasi, maksimum sekitar 12 slide. Harus ada jarak antara tiap sediaan untuk mencegah terjadinya kontaminasi antar sediaan. 25.2. Cara pewarnaan : 1) Letakkan sediaan dahak yang telah difiksasi pada rak dengan hapusan dahak menghadap keatas. 2) Teteskan larutan Carbol Fuchsin 0,3% pada hapusan dahak sampai menutupi seluruh permukaan sediaan dahak. 3) Panaskan dengan nyala api spiritus sampai keluar uap selama 3-5 menit. Zat warna tidak boleh mendidih atau kering. Apabila mendidih atau kering maka carbol fuchsin akan terbentuk kristal (partikel kecil) yang dapat terlihat seperti kuman TBC. 4) Singkirkan api spiritus. Diamkan sediaan selama 5 menit. 5) Bilas sediaan dengan air mengalir pelan sampai zat warna yang bebas terbuang. 6) Teteskan sediaan dengan asam alkohol (HCl Alkohol 3%) sampai warna merah fuchsin hilang. 7) Bilas dengan air mengalir pelan. 8) Teteskan larutan Methylen Blue 0,3% pada sediaan sampai menutupi seluruh permukaan 9) Diamkan 10-20 detik. 10) Bilas dengan air mengalir pelan. 11) Keringkan sediaan diatas rak pengering di udara terbuka (jangan dibawah sinar matahari langsung).
xxiii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
26. PEMBACAAN SEDIAAN Sediaan yang telah diwarnai dan sudah kering diperiksa dibawah mikroskop binokuler. 26.1. Pembacaan sediaan dahak: 1) Cari lebih dahulu lapang pandang dengan objektif 10 x 2) Teteskan satu tetes minyak emersi diatas hapusan dahak. 3) Periksa dengan menggunakan lensa okuler 10 x dan objektif 100x 4) Carilah Basil Tahan Asam (BTA) yang berbentuk batang berwarna merah. 5) Periksa paling sedikit 100 lapang pandang atau dalam waktu kurang lebih 10 menit, dengan cara menggeserkan sediaan menurut arah seperti gambar dibawah ini.
6) Sedian dahak yang telah diperiksa kemudian direndam dalam xylol selama 15-30 menit, lalu disimpan dalam kotak sediaan. Bila menggunakan anisol, sediaan dahak tidak perlu direndam dalam xylol. 8.2 Pembacaan hasil: Pembacaan hasil pemeriksaan sediaan dahak dilakukan dengan menggunakan skala IUATLD sebagai berikut: 1) Tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang, disebut negatif. 2) Ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang, ditulis jumlah kuman yang ditemukan. 3) Ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapang pandang, disebut + atau (1+). 4) Ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapang pandang, disebut ++ atau (2+), minimal dibaca 50 lapang pandang. 5) Ditemukan > 10 BTA dalam 1 lapang pandang, disebut +++ atau (3+), minimal dibaca 20 lapang pandang. Penulisan gradasi hasil bacaan penting untuk menunjukkan keparahan penyakit dan tingkat penularan penderita tersebut. Catatan: Bila ditemukan 1-3 BTA dalam 100 lapang pandang, pemeriksaan harus diulang dengan spesimen dahak yang baru. Bila hasilnya tetap 1-3 BTA, hasilnya dilaporkan negatif. Bila ditemukan 4-9 BTA, dilaporkan positif.
xxiv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
27. PENCATATAN HASIL PEMBACAAN Hasil bacaan harus dicatat dalam buku register laboratorium (TB.04). Tiap catatan hasil pembacaan, diberi nomor register laboratorium sesuai urutan tanggal pemeriksaan. Alasan pemeriksaan (apakah untuk diagnosis atau untuk follow-up pengobatan) penting untuk dicantumkan. Hasil pemeriksaan dengan memasukkan 1+, 2+ atau 3+ sesuai gradasi hasil pembacaan ditulis dengan tanda rumput pada kotak yang sesuai. 28. PENYIMPANAN SEDIAAN UNTUK DI CROSS CHECK Dalam menjaga mutu pemeriksaan dahak, perlu dilakukan pemeriksaan cross check dari sediaan yang sudah diperiksa. Sebab itu, semua sediaan (untuk diagnosa dan follow-up) yang sudah selesai diperiksa, baik sediaan yang BTA Positif maupun sediaan yang BTA Negatif, harus disimpan dengan baik dalam suatu kotak sediaan. Sediaan positif harus disimpan terpisah dari sediaan yang negatif. Sekali setiap triwulan, pada waktu melakukan supervisi, petugas kabupaten / kota akan mengambil satu sediaan untuk setiap penderita dari semua penderita BTA positif dan satu sediaan untuk setiap penderita dari 10% penderita BTA negatif. Sediaan tersebut diambil secara acak untuk dicross check ke Balai Laboratorium Kesehatan atau laboratorium rujukan lain yang ditunjuk. Setelah pengambilan sample untuk di cross check, sisa sediaan dapat dimusnahkan dengan memperhatikan prosedur keamanan dan keselamatan kerja. Tatacara pelaksanaan cross check akan diterangkan dalam bab tersendiri. 29. PEMBUANGAN LIMBAH LABORATORIUM Pot dengan sisa-sisa dahak yang sudah selesai diperiksa (tutup pot harus dilepas) dan bahan-bahan lain yang telah terkontaminasi dengan dahak harus direndam kedalam suatu tempat penampungan (ember) yang telah berisi larutan sodium hipoklorit 5% atau larutan fenol 5% selama semalam. Alkohol tidak dapat mengganti fungsi dari sodium hipoklorit atau fenol tersebut diatas. Bila tersedia otoklaf, bahan-bahan tersebut selanjutnya dimasukan kedalam otoklaf dan disteril pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Bila tidak tersedia otoklaf, bahan-bahan tersebut direbus sampai mendidih selama 60 menit. Selanjutnya dibakar atau dikubur. Kaca sediaan yang telah dipakai tidak dapat dipakai ulang, harus dibuang. Cara pembuangannya yaitu dengan dikubur. 30. KEAMANAN KERJA DI LABORATORIUM Spesimen dahak dan bahan kimia lainnya, misalnya reagens, bila tidak dikelola dengan benar, akan mempunyai risiko terhadap gangguan kesehatan atau penyakit bagi petugas dan masyarakat disekitar laboratorium tersebut. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya risiko tersebut, maka setiap petugas harus melaksanakan ketentuan dan prosedur keamanan kerja di laboratorium dengan taat, baik
xxv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
dan benar, mulai dari pengumpulan dahak, pembuatan sediaan dan pembuangan sisa dahak. Ketentuan penting yang harus diperhatikan, petugas laboratorium: 30.1. Pakailah jas laboratorium saat berada dalam ruang pemeriksaan atau di ruang laboratorium. Tinggalkan jas laboratorium di ruang laboratorium setelah selesai bekerja. 30.2. Semua spesimen dahak harus dianggap infeksius (sumber penular), oleh karena itu harus ditangani dengan sangat hati-hati. 30.3. Semua bahan kimia harus dianggap berbahaya, oleh karena itu harus ditangani dengan hati hati. 30.4. Dilarang makan, minum dan merokok di dalam laboratorium 30.5. Dilarang menyentuh mulut dan mata pada saat sedang bekerja. 30.6. Dilarang memipet dengan mulut. Gunakan alat bantu pipet (pipette bulb) atau pipet otomatis 30.7. Bersihkan semua peralatan bekas pakai dengan desinfektans setiap kali selesai bekerja. 30.8. Desinfektan yang sangat baik untuk membunuh mikroorganisme adalah sodium hipoklorit dengan konsentrasi umum: 1-5 gram per liter zat chlor aktif. 30.9. Hindari terjadinya tumpahan aerosol atau percikan bila sedang bekerja. Droplet dapat terjadi pada saat membuka pot dahak, membuat hapusan sediaan, membakar ose, dan membuang pot dahak bekas. 30.10. Bersihkan meja kerja dengan desinfektan setiap kali selesai bekerja 30.11. Cuci tangan dengan sabun atau desinfektan setiap kali selesai kerja. 31. PEMANTAPAN MUTU LABORATORIUM Untuk menjamin ketepatan dan ketelitian hasil pemeriksaan sediaan hapus dahak, harus dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi: 31.1. Pendidikan dan pelatihan 31.2. Pelaksanaan pemantapan mutu internal: 1) persiapan penderita, 2) pengambilan dan penanganan spesimen, 3) pemeliharaan alat/mikroskop, 4) uji kualitas reagen/larutan pewarna, 5) penyusunan prosedur tetap, dan 6) pencatatan serta pelaporan. 31.3. Melakukan validasi hasil pemeriksaan/cross check. 31.4. Melaksanakan audit. 31.5. Mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal mikroskopis BTA. 31.6. Melaksanakan praktek laboratorium yang benar. 31.7. Melaksanakan praktek pembuatan reagen Ziehl Neelsen yang benar.
xxvi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
32. PEMELIHARAAN MIKROSKOP Mikroskop merupakan alat diagnostik utama dalam penanggulangan TBC. Oleh sebab itu perlu penanganan dan pemeliharaan yang baik, terutama lensanya, yang merupakan bagian terpenting. Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1) Letakkan dan simpan mikroskop pada tempat yang kering, bebas debu dan bebas getaran Getaran dapat merusak mikroskop. Jangan meletakkan mikroskop satu meja dengan alat sentrifusi (centrifuge) atau diatas lemari es (refrigerator). Hindarkan mikroskop dari sinar matahari langsung. Bila mikroskop tidak digunakan, tutuplah dengan kain/plastik penutupnya atau masukkan kedalam kotaknya supaya terhindar dari debu. Jangan menyimpan mikroskop ditempat yang lembab, sebab lensa dapat berjamur sehingga mengganggu pandangan. Keadaan lembab juga dapat mengakibatkan karatan (korosif) pada bagian-bagian mikroskop yang terbuat dari logam. Simpan mikroskop di dalam kontak penyimpan mikroskop, dengan cahaya lampu (5 watt) atau serbuk pengering (silica gel) dalam jumlah yang cukup. Perlu diingat, bubuk pengering (silica gel) tersebut berwarna biru bila masih kering (masih aktif bekerja), dan akan menjadi warna merah-muda bila sudah basah (tidak aktif lagi). Oleh karena itu, begitu silica gel tersebut berwarna merah-muda, segera ganti dengan silica gel yang baru atau panaskan sampai berwarna biru kembali. 2) Jagalah supaya mikroskop dan lensanya tetap bersih. Selalu bersihkan mikroskop dengan kertas pembersih lensa sebelum dan sesudah digunakan. Selalu bersihkan lensa objektif 100 x dari oli emersi setelah selesai digunakan. Jangan gunakan alkohol atau spiritus untuk membersihkan lensa, sebab lensa dapat rusak. Jangan menyentuh lensa objektif 100 x pada kaca sediaan. Bersihkan semua lensa dengan kertas pembersih lensa. Bila perlu, kertas pembersih lensa tersebut dapat dibasahkan dengan xylol. Jangan bersihkan lensa dengan kain biasa.
BAB VII CROSS CHECK SEDIAAN DAHAK
33. MAKSUD DAN PRINSIP PEMERIKSAAN CROSS CHECK
xxvii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Maksud :
Pemeriksaan cross check / uji silang merupakan salah satu kegiatan pemantapan mutu laboratorium dengan maksud untuk mengetahui kualitas hasil pemeriksaan sediaan dahak BTA. Sediaan dahak yang telah diperiksa oleh laboratorium pertama (PRM, PPM, RS, dll), dikirim ke laboratorium rujukan yang ditunjuk untuk melakukan cross check, dan laboratorium rujukan tidak boleh mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium pertama.
Prinsip :
34. CARA PENGAMBILAN SAMPLE SEDIAAN UNTUK DI CROSS CHECK
Sekali setiap triwulan (pada waktu melakukan supervisi) petugas kabupaten / kota akan mengambil sample sediaan dahak yang telah diperiksa dan disimpan oleh laboratorium pertama (PRM, PPM, RS, dll), meliputi: Satu sediaan dari setiap penderita BTA positif. Untuk penderita BTA negatif, diambil 10% secara acak. Diambil satu sediaan untuk setiap penderita yang terpilih. Setelah sample untuk di cross check diambil, sisa sediaan dapat dimusnahkan (sesuai prosedur pembuangan limbah laboratorium, sebagaimana dijelaskan dalam Bab V). Pengambilan sediaan untuk di cross check harus dengan mengisi formulir TB.12 yang dibuat dalam 2 rangkap. Lembar ke 1 (yang akan dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan atau laboratorium rujukan lain yang ditunjuk) hanya diisi kolom 1, 2, 3, dan 4. Kolom 5 dan 6 (hasil pemeriksaan laboratorium pertama) tidak perlu diisi. Lembar ke 2 (untuk disimpan di Dinas Kesehatan kabupaten / kota) diisi kolom 1 s/d 6. Lembar ke 2 ini dipakai untuk analisa hasil cross check setelah hasil pemeriksaaan dari BLK atau dari laboratorium rujukan lainnya sudah diterima.
35. ASPEK YANG DINILAI DALAM CROSS CHECK
Penilaian cross check harus dilakukan dalam 3 aspek, yaitu: Menilai kualitas hapusan sediaan, Menilai kualitas pewarnaan, dan Menilai kualitas pembacaan. Penilaian kualitas hapusan sediaan dan kualitas pewarnaan dilakukan baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Penilaian kualitas sediaan dinilai dari segi ukuran, ketebalan dan kerataan sediaan hapus.
xxviii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
36. ALUR CROSS CHECK
Pengiriman sediaan untuk cross check dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten / kota langsung ke Balai Laboratorium Kesehatan atau laboratorium rujukan lain yang ditunjuk untuk melakukan cross check, dengan dilampiri formulir TB.12 yang tidak mencantumkan hasil pemeriksaan laboratorium pemeriksa pertama (PRM, PPM, RS, dll). Hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan atau laboratorium rujukan lain diisi dalam kolom pemeriksan laboratorium yang melakukan cross check (kolom 7 s/d 12) dari formulir TB.12, dan dikirim kembali ke Dinas Kesehatan kabupaten / kota untuk dianalisa hasil cross check tersebut.
37. CARA MENGHITUNG HASIL CROSS CHECK
Setelah Dinas Kesehatan kabupaten / kota menerima hasil pemeriksaan dari BLK atau dari laboratorium rujukan lain, petugas kabupaten / kota harus melakukan perhitungan hasil cross check. Caranya yaitu membandingkan hasil BLK dengan hasil pemeriksaan laboratorium pertama (PRM, PPM, RS, dll) yang disimpan di Dinas Kesehatan kabupaten / kota. Perhitungan meliputi persentase positif palsu, persentase negatif palsu, dan angka kesalahan (error rate). Caranya sebagai berikut:
37.1.
Positif palsu:
37.2.
37.3.
38. INTERPRETASI HASIL CROSS CHECK
xxix
J J J
Negatif palsu:
Angka kesalahan (error rate):
X 100 %
l h l h l h
X 100 %
X 100 %
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Sama seperti menilai indikator angka kesembuhan (cure rate) dan cakupan penemuan, maka penilaian angka kesalahan laboratorium (error rate), persentase positif palsu, dan persentase negatif palsu dinilai per kabupaten / kota. Apabila error rate < 5%, dan positif palsu dan negatif palsu kedua-duanya juga < 5%, maka mutu pemeriksaan dahak di kabupaten / kota tersebut dinilai bagus. Perhitungan error rate per PRM / PPM / RS diperlukan untuk mengetahui laboratorium mana yang perlu mendapat prioritas bimbingan atau petugasnya perlu magang di BLK.
39. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT HASIL CROSS CHECK
Analisa hasil cross check harus diumpan balikkan ke laboratorium pemeriksa pertama (PRM, PPM, RS, dll) dengan tembusan ke BLK atau laboratorium rujukan lain dan Dinas Kesehatan Propinsi. Hasil cross check ini harus ditindak lanjuti. Bila hasil cross check menunjukan angka kesalahan (error rate) lebih besar dari 5%, unit-unit terkait harus meneliti lebih lanjut apa kemungkinan penyebabnya. Penelitian ini harus dilakukan secara cermat terhadap berbagai aspek dalam proses pemeriksaan dahak, misalnya: kualitas sediaan, kualitas reagens Ziehl Neelsen, kualitas mikroskop yang digunakan, serta ketrampilan petugas laboratorium. Kesalahan-kesalahan ini harus segera di tindak-lanjuti, misalnya memberikan pelatihan ulang kepada petugas (magang) di BLK, penyediaan reagens yang berkualitas, atau perbaikan mikroskop, dan lain-lain. Catatan: Bila pada pemeriksaan cross check didapatkan angka kesalahan yang tinggi dengan kualitas pewarnaan yang jelek (warna sediaan memudar) maka perhitungan positif palsu, negatif palsu dan error rate dilakukan setelah restaining. Balai Laboratorium Kesehatan atau laboratorium rujukan lain yang melakukan cross check akan memberi umpan balik pengaruh faktor pewarnaan sediaan terhadap tingginya angka kesalahan (error rate).
xxx
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Bagan-3 ALUR RUJUKAN CROSS CHECK
Laboratorium yang melakukan cross check: Balai Laboratorium Kesehatan Laboratorium rujukan lain.
Dinas Kesehatan Propinsi
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
PRM/PPM/UPK lainnya PRM/PPM/UPK Lainnya PRM/PPM/UPK Lainnya
Keterangan: : Jalur pengambilan/pengiriman sediaan untuk di cross check dilakukan oleh kabupaten / kota : Jalur penyampaian hasil cross check. : Jalur pengiriman umpan balik analisis hasil cross check.
xxxi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
BAB VIII PENYULUHAN TUBERKULOSIS
Penyuluhan kesehatan yang merupakan bagian dari promosi kesehatan adalah rangkaian kegiatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan dimana individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan dapat hidup sehat dengan cara memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatannya. Penyuluhan TBC perlu dilakukan karena masalah TBC banyak berkaitan dengan masalah pengetahuan dan perilaku masyarakat. Tujuan penyuluhan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan peranserta masyarakat dalam penanggulangan TBC. Penyuluhan TBC dapat dilaksanakan dengan menyampaikan pesan penting secara langsung ataupun menggunakan media. Penyuluhan langsung bisa dilakukan: - perorangan - kelompok Penyuluhan tidak langsung dengan menggunakan media, dalam bentuk: - bahan cetak seperti leaflet, poster atau spanduk - media massa, yang dapat berupa Media cetak seperti koran, majalah. Media elektronik seperti radio dan televisi.
Dalam program penanggulangan TBC, penyuluhan langsung perorangan sangat penting untuk menentukan keberhasilan pengobatan penderita. Penyuluhan ini ditujukan kepada suspek, penderita dan keluarganya, supaya penderita menjalani pengobatan secara teratur sampai sembuh. Bagi anggota keluarga yang sehat dapat menjaga, melindungi dan meningkatkan kesehatannya, sehingga terhindar dari penularan TBC. Penyuluhan dengan menggunakan bahan cetak dan media massa dilakukan untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, untuk mengubah persepsi masyarakat tentang TBC dari suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan memalukan, menjadi suatu penyakit yang berbahaya, tapi dapat disembuhkan. Bila penyuluhan ini berhasil, akan meningkatkan penemuan penderita secara pasif. Penyuluhan langsung dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, para kader dan PMO, sedangkan penyuluhan kelompok dan penyuluhan dengan media massa selain dilakukan oleh tenaga kesehatan, juga oleh para mitra dari berbagai sektor, termasuk kalangan media massa. Selanjutnya secara lebih rinci, penyuluhan TBC dilakukan sebagai berikut:
40. PENYULUHAN LANGSUNG PERORANGAN
xxxii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Cara penyuluhan langsung perorangan lebih besar kemungkinan untuk berhasil dibanding dengan cara penyuluhan melalui media. Dalam penyuluhan langsung perorangan, unsur yang terpenting yang harus diperhatikan adalah membina hubungan yang baik antara petugas kesehatan (dokter, perawat, dll) dengan penderita. Penyuluhan ini dapat dilakukan di rumah, di puskesmas, posyandu, dan lain-lain sesuai kesempatan yang ada. Supaya komunikasi dengan penderita bisa berhasil, petugas harus menggunakan bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh penderita. Gunakan istilah-istilah setempat yang sering dipakai masyarakat untuk penyakit TBC dan gejala-gejalanya. Supaya komunikasi berhasil baik, petugas kesehatan harus melayani penderita secara ramah dan bersahabat, penuh hormat dan simpati, mendengar keluhan-keluhan mereka, serta tunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan kesembuhan mereka. Dengan demikian, penderita mau bertanya tentang hal-hal yang masih belum dimengerti. Penyuluhan langsung perorangan ini dapat dianggap berhasil bila: penderita bisa menjelaskan secara tepat tentang riwayat pengobatan sebelumnya. penderita datang berobat secara teratur sesuai jadwal pengobatan. anggota keluarga penderita dapat menjaga dan melindungi kesehatannya. 1.1. Hal-hal penting yang disampaikan pada kunjungan pertama Dalam kontak pertama dengan penderita, terlebih dulu dijelaskan tentang penyakit apa yang dideritanya, kemudian Petugas Kesehatan berusaha memahami perasaan penderita tentang penyakit yang diderita serta pengobatannya. Petugas Kesehatan seyogyanya berusaha mengatasi beberapa faktor manusia yang dapat menghambat terciptanya komunikasi yang baik. Faktor yang menghambat tersebut, antara lain: Ketidaktahuan penyebab TBC, dan cara penyembuhannya. Rasa takut yang berlebihan terhadap TBC yang menyebabkan timbulnya reaksi penolakan. Stigma sosial yang mengakibatkan penderita merasa takut tidak diterima oleh keluarga dan temannya. Menolak untuk mengajukan pertanyaan karena tidak mau ketahuan bahwa ia tidak tahu tentang TBC. Pada kontak pertama ini petugas kesehatan harus menyampaikan beberapa informasi penting tentang TBC, antara lain: a. Apa itu TBC? Jelaskan bahwa TBC adalah penyakit menular dan bukan penyakit keturunan. Tenangkan hati penderita dengan menjelaskan bahwa penyakit ini dapat disembuhkan bila penderita menjalani seluruh pengobatan seperti yang dianjurkan. b. Riwayat pengobatan sebelumnya Jelaskan kepada penderita bahwa riwayat pengobatan sebelumnya sangat penting untuk menentukan secara tepat paduan OAT yang akan diberikan. Salah pengertian akan akan mengakibatkan pemberian paduan OAT yang salah.
xxxiii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Petugas Kesehatan harus menjelaskan bahwa pengobatan pada seorang penderita baru berbeda dengan pengobatan pada penderita yang sudah pernah diobati sebelumnya. c. Bagaimana cara pengobatan TBC Jelaskan kepada penderita tentang: o Tahapan pengobatan (tahap intensif dan tahap lanjutan) o Frekwensi menelan obat (tiap hari atau 3 kali seminggu) o Cara menelan obat (dosis tidak dibagi) o Lamanya pengobatan untuk masing-masing tahap d. Pentingnya pengawasan langsung menelan obat Perlu disampaikan pentingnya pengawasan langsung menelan obat pada semua penderita TBC, terutama pada pengobatan tahap awal (intensif). Bila tahap ini dapat dilalui dengan baik, maka besar kemungkinan penderita dapat disembuhkan. Penderita perlu didampingi oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO). Diskusikan dengan penderita bahwa PMO tersebut sangat penting untuk mendampingi penderita agar dicapai hasil pengobatan yang optimal. e. Bagaimana penularan TBC Jelaskan secara singkat bahwa kuman TBC dapat menyebar ke udara waktu penderita bersin atau batuk. Orang disekeliling penderita dapat tertular karena menghirup udara yang mengandung kuman TBC. Oleh karena itu, penderita harus menutup mulut bila batuk atau bersin dan jangan membuang dahak disembarang tempat. Jelaskan pula bila ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala TBC (batuk, berat badan menurun, kelesuan, demam, berkeringat malam hari, nyeri dada, sesak nafas, hilang nafsu makan, batuk dengan dahak campur darah), sebaiknya segera memeriksakan diri ke unit pelayanan kesehatan. Setiap anak balita yang tinggal serumah atau kontak erat dengan penderita TBC BTA positif segera dibawa ke unit pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan, sebab anak balita sangat rentan terhadap kemungkinan penularan dan jatuh sakit. 1.2. Hal-hal yang perlu ditanyakan pada kunjungan berikutnya Pada kunjungan berikutnya, sisihkan waktu beberapa menit untuk menanyakan halhal yang telah dijelaskan pada kunjungan lalu, hal ini untuk memastikan bahwa penderita sudah mengerti. Beberapa hal penting yang perlu dibahas dengan penderita pada kunjungan berikut, adalah: a. Cara menelan OAT. b. Jumlah obat dan frekuensi menelan OAT. c. Apakah terjadi efek samping OAT, seperti: Kemerahan pada kulit Kuning pada mata dan kulit
xxxiv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Gejala seperti flu (demam, kedinginan dan pusing) Nyeri dan pembengkakan sendi, terutama pada sendi pergelangan kaki dan pergelangan tangan Gangguan penglihatan Warna merah / orange pada air seni Gangguan keseimbangan dan pendengaran Rasa mual, gangguan perut sampai muntah Rasa kesemutan / terbakar pada kaki. Jelaskan kepada penderita, bila mengalami hal-hal tersebut, beritahu kepada petugas kesehatan atau PMO supaya dapat segera diatasi.
d. Pentingnya dan jadwal pemeriksaan ulang dahak. e. Arti hasil pemeriksaan ulang dahak: negatif atau tetap positif. f. Apa yang dapat terjadi bila pengobatan tidak teratur atau tidak lengkap. 2. PENYULUHAN KELOMPOK Penyuluhan kelompok adalah penyuluhan TBC yang ditujukkan kepada sekelompok orang (sekitar 15 orang), bisa terdiri dari penderita TBC dan keluarganya. Penggunaan flip chart (lembar balik) dan alat bantu penyuluhan lainnya sangat berguna untuk memudahkan penderita dan keluarganya menangkap isi pesan yang disampaikan oleh petugas. Dengan alat peraga (dalam gambar / simbol) maka isi pesan akan lebih mudah dan lebih cepat dimengerti. Gunakan alat bantu penyuluhan dengan tulisan dan atau gambar yang singkat dan jelas. 3. PENYULUHAN MASSA Penyakit menular termasuk TBC bukan hanya merupakan masalah bagi penderita, tetapi juga masalah bagi masyarakat, oleh karena itu keberhasilan penanggulangan TBC sangat tergantung tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pesan-pesan penyuluhan TBC melalui media massa (surat kabar, radio, dan TV) akan menjangkau masyarakat umum. Bahan cetak berupa leaflet, poster, billboard hanya menjangkau masyarakat terbatas, terutama pengunjung sarana kesehatan. Penyampaian pesan TBC perlu memperhitungkan kesiapan unit pelayanan, misalnya tenaga sudah dilatih, obat tersedia dan sarana laboratorium berfungsi. Hal ini perlu dipertimbangkan agar tidak mengecewakan masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Penyuluhan massa yang tidak dibarengi kesiapan UPK akan menjadi bumerang (counter productive) terhadap keberhasilan penanggulangan TBC.
xxxv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
4. KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN TBC 4.1. TBC tidak hanya merupakan masalah kesehatan tetapi juga masalah sosial. 4.2. Perlu keterlibatan berbagai pihak dan sektor dalam masyarakat, termasuk kalangan swasta, organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan serta LSM dalam penanggulangan TBC. 4.3. Sosialisasi dan advokasi program penanggulangan TBC perlu dilaksanakan ke berbagai pihak dengan tujuan memperoleh dukungan. 5. ADVOKASI Advokasi merupakan salah satu kegiatan penting dalam promosi kesehatan. Tujuan advokasi adalah menarik perhatian para tokoh penting atau tokoh kunci, untuk memperoleh dukungan politik agar dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat. Tahap-tahap yang perlu dipersiapkan untuk merencanakan kegiatan advokasi: - Analisa situasi, - Memilih strategi yang tepat, - Mengembangkan bahan- bahan yang perlu disajikan kepada sasaran, dan - Mobilisasi sumber dana.
Pesan-pesan tentang TBC harus diarahkan pada: Apa itu TBC dan bagaimana penyakit ini menular?. Gejala-gejala TBC dan pentingnya diagnosis dini. Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang memberi pelayanan TBC. Tatalaksana pengobatan TBC. Pentingnya berobat teratur sampai dengan selesai dan bahayanya bila berobat tidak teratur. Cara pencegahan TBC.
xxxvi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam sistem informasi penanggulangan TBC. Untuk itu pencatatan & pelaporan perlu dibakukan berdasar klasifikasi dan tipe penderita. Semua unit pelaksana program penanggulangan TBC harus melaksanakan suatu sistem pencatatan dan pelaporan yang baku. Formulir pencatatan dan laporan yang digunakan dalam penanggulangan TBC Nasional adalah: TB 01. Kartu pengobatan TB TB 02. Kartu identitas penderita TB 03. Register TB kabupaten TB 04. Register Laboratorium TB TB 05. Formulir permohonan laboratorium TB untuk pemeriksaan dahak TB 06. Daftar tersangka penderita (suspek) yang diperiksa dahak SPS TB 07. Laporan Triwulan Penemuan Penderita Baru dan Kambuh TB 08. Laporan Triwulan Hasil Pengobatan Penderita TB Paru yang terdaftar 12 - 15 bulan lalu TB 09. Formulir rujukan/pindah penderita TB 10. Formulir hasil akhir pengobatan dari penderita TB pindahan TB 11. Laporan Triwulan Hasil Pemeriksaan Dahak Akhir Tahap Intensif untuk penderita terdaftar 3 - 6 bulan lalu TB 12. Formulir Pengiriman Sediaan Untuk Cross Check TB 13. Laporan Penerimaan dan Pemakaian OAT di kabupaten Disamping formulir tersebut diatas terdapat formulir sebagai berikut: Rekapitulasi TB.07 kabupaten / kota ( blok 1 & blok 2 ) Rekapitulasi TB.08 kabupaten / kota (Penderita Baru BTA positif, Penderita Kambuh dan Penderita Baru BTA negatif Rntgen positif) Rekapitulasi TB.12 kabupaten / kota dan propinsi Rekapitulasi TB.11 Per kabupaten / kota dan propinsi (Penderita Baru BTA Positif, Penderita Kambuh, dan Gagal). Rekapitulasi TB.13 propinsi. Pencatatan dan pelaporan pada masing-masing tingkat pelaksana. PENCATATAN DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN UPK misalnya Puskesmas, Rumah Sakit, BP4, klinik dan dokter praktek swasta dalam melaksanakan pencatatan dapat menggunakan formulir sebagai berikut: Daftar tersangka penderita (suspek) yang diperiksa dahak SPS (TB.06), Formulir permohonan laboratorium TB untuk pemeriksaan dahak (TB.05),
xxxvii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Kartu pengobatan TB (TB.01), Kartu identitas penderita (TB.02), Formulir rujukan/pindah penderita (TB.09) Formulir hasil akhir pengobatan dari penderita TB pindahan (TB.10). UPK diharuskan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilaksanakan dan tidak diwajibkan membuat laporan. Petugas kabupaten/kota akan mengambil data yang dibutuhkan dan mengisi dalam buku Register TB Kabupaten (Form TB.03) sebagai bahan laporan yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin. UPK yang banyak penderitanya, misalnya rumah sakit, dapat menggunakan buku pencatatan seperti Buku Register TB Kabupaten (TB.03), tetapi untuk nomor register diisi sesuai dengan nomor register yang diberikan oleh kabupaten / kota. PENCATATAN DI LABORATORIUM PRM / PPM / RS / BP4 Laboratorium yang melakukan pewarnaan dan pembacaan sedian dahak BTA menggunakan formulir pencatatan sebagai berikut: Register Laboratorium TB (Formulir TB.04) Formulir Permohonan Laboratorium TB Untuk Pemeriksaan Dahak (TB.05) bagian bawah (mengisi hasil pemeriksaan).
PENCATATAN DAN PELAPORAN DI KABUPATEN / KOTA Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan sebagai berikut: Register TB kabupaten (Formulir TB.03) Laporan Triwulan Penemuan Penderita Baru dan Kambuh (Formulir TB.07) Laporan Triwulan Hasil Pengobatan (Formulir TB.08) Laporan Triwulan Hasil Konversi Dahak Akhir Tahap Intensif (Formulir TB.11) Formulir Pemeriksaan Sediaan untuk Cross Check (Formulir TB.12) Rekapitulasi TB.12 kabupaten (Analisis Hasil Cross Check kabupaten) Laporan Penerimaan dan Pemakaian OAT di daerah Kabupaten/Kota (Formulir TB.13)
PENCATATAN DAN PELAPORAN DI PROPINSI Propinsi menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan sebagai berikut: Rekapitulasi TB.07 blok 1 per kabupaten/ kota. Rekapitulasi TB.07 blok 2 per kabupaten/ kota. Rekapitulasi TB.08 yang dibuat tersendiri untuk tiap tipe penderita per kabupaten/ kota. Rekapitulasi TB.11 yang dibuat tersendiri untuk tiap tipe penderita per kabupaten/ kota. Rekapitulasi TB.12 propinsi (Rekapitulasi Analisis Hasil Cross Check propinsi) per kabupaten/ kota.
xxxviii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
CONTOH FORMULIR PENCATATAN PELAPORAN YANG DIGUNAKAN Lihat Lampiran.
41. PETUNJUK CARA PENGISIAN FORMULIR PENCATATAN DAN PELAPORAN
Formulir TB.01 (Kartu Pengobatan TBC) Kartu ini disimpan di Unit Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, RS, BP4, dan lain-lain) dimana penderita tersebut mendapat pengobatan. Nama Penderita : Nama lengkap Alamat Lengkap : Tulis lengkap Nama Pengawas Pengobatan/ PMO : Tulis lengkap, kemudian dalam kurung tulis status PMO tersebut, misalnya: (petugas kesehatan), (kader), dll. Alamat lengkap PMO : Tulis lengkap. Tahun : Tahun mulai pengobatan. No. Reg. TB Kabupaten : Diisi oleh wasor, sesuai nomor register TB kabupaten / kota (TB.03). Nama Unit Pelayanan Kesehatan : Nama unit yang memberi pengobatan. Jenis kelamin : Beri tanda pada kotak yang sesuai. Umur : Tulis umur penderita dalam tahun. Parut BCG : Beri tanda pada kotak yang sesuai. Riwayat Pengobatan Sebelumnya : Beri tanda pada kotak yang sesuai. Klasifikasi Penyakit : Beri tanda pada kotak yang sesuai. Jika pilihan pada kotak Ekstra Paru, tulislah dimana lokasinya, misalnya kelenjar limfe. Catatan : Tulis hasil pemeriksaan lain yang dilakukan misalnya rontgen, tulis nomor foto, tanggal pemeriksaan, dan kesimpulan hasil bacaannya, demikian juga Hasil pemeriksaan lain seperti biopsi dll. Tipe Penderita : Beri tanda pada kotak yang sesuai. Jika pilihan pada kotak lain-lain, sebutkan tipenya, misalnya Gagal. Pemeriksaan Kontak Serumah: Tulis nama, jenis kelamin, umur dari semua orang yang tinggal serumah dengan penderita BTA positif. Lakukan pemeriksaan sesuai petunjuk, kemudian tulislah tanggal dan hasil pemeriksaan tersebut. Hasil Pemeriksaan Dahak : Hasil tersebut harus ditulis sesuai baris dari bulan pemeriksaan yang dilakukan, misalnya baris bulan 0 (awal) untuk pemeriksaan awal (kepentingan
xxxix
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Tanggal No. Reg. Lab BTA BB (kg) Tahap Intensif Kolom Pemberian Obat
: : : : : :
diagnosis). Baris bulan ke 2 untuk pemeriksaan pada akhir bulan ke 2, dan seterusnya. Adalah tanggal gradasi positif tertinggi. Nomor Register Lab sesuai formulir TB.05 yang dikirim kembali ke anda. Tulis hasil tingkat positif (gradasi) yang tertinggi (misal : ++ = ditulis 2+, +++ = ditulis 3+). Berat badan penderita (dalam kg). Beri tanda pada kotak kategori obat yang sesuai. Di kolom bulan, tulis nama bulan pengobatan. Di kotak-kotak tanggal, beri tanda jika penderita datang mengambil obat atau pengobatan dibawah pengawasan petugas. Jika obat dibawa pulang dan ditelan sendiri dirumah, beri tanda (garis lurus) pada kotak-kotak tersebut sebanyak jumlah obat yang diberikan, misalnya diberi 4 blister maka beri tanda garis lurus pada 4 kotak.
6 7 8 9 10 11 12 13
Contoh: tanggal tanda
Halaman ke 2 (bagian belakang) formulir TB.01: Tahap Lanjutan Kolom pemberian obat : Beri tanda pada kotak kategori obat yang sesuai. : Cara pengisiannya hampir sama seperti pada tahap intensif. Pada kotak tanggal beri tanda jika penderita datang mengambil obat atau pengobatan dibawah pengawasan petugas kesehatan. Beri tanda (strip) pada setiap kotak-tanggal dimana obat akan diminum dan diberikan untuk dibawa pulang.
6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18
Contoh: tanggal tanda Catatan Hasil Akhir Pengobatan
: Disediakan untuk menulis informasi lain yang dianggap penting dari penderita tsb. : Tulislah tanggal hasil akhir pengobatan dalam kotak yang sesuai.
Formulir TB.02 (Kartu Identitas Penderita):
xl
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Kartu TB.02 disimpan oleh penderita. Selain mencatat identitas penderita, kartu ini dipakai pula untuk mencatat paduan obat yang diberikan kepada penderita, jumlah obat yang telah diberikan kepada penderita, tanggal harus kembali, tanggal pemeriksaan ulang dahak, dan catatan lain oleh dokter atau perawat. Cara pengisian halaman depan cukup jelas. Cara pengisian halaman belakang: Tanggal Tahap pengobatan : Tulis tanggal kunjungan sekarang. : Tulis intensif atau lanjutan sesuai dengan tahap pengobatan yang diberikan. Jumlah obat yang diberikan : Tulis jumlah blister yang diberikan termasuk jumlah yang dibawa pulang. Tanggal harus kembali : Tulis tanggal yang diminta penderita harus kembali untuk mendapat pengobatan. Tanggal Perjanjian Untuk Pemeriksaan Dahak Ulang : Cukup jelas. Catatan penting: oleh dokter dan perawat : Tulis catatan lain yang penting diketahui penderita. Formulir TB.03 (Register TB Kabupaten): Buku ini dipakai oleh Wasor TBC kabupaten/kota untuk mendaftar (mencatat) semua penderita yang diobati di unit pelayanan kesehatan (UPK) dalam kabupaten/ kota yang bersangkutan. Setiap penderita yang terdaftar akan diberi nomor register kabupaten. Pemberian pengobatan kepada penderita harus segara dimulai meskipun kartu penderita tersebut belum mendapat nomor register kabupaten. Cara pengisian formulir TB.03: Tahun Tanggal registrasi No. Reg. TB. Kab : Tulis tahun yang sedang berjalan. : Tulis tanggal pada waktu penderita tersebut di register. : Tulis nomor register tersebut dengan 3 digit, mulai dengan 001 setiap permulaan tahun anggaran. Nomor ini ditulis berurutan sesuai baris-baris. Contoh: sewaktu berkunjung ke Puskesmas Waringin terdapat 5 penderita TB yang sedang berobat tapi belum terdaftar. Misalnya dalam buku register anda nomor register terakhir adalah 022, maka catatlah data pada kartu pengobatan TB-01 kedalam buku register kabupaten TB-03, beri nomer register kabupaten dengan nomor 023, 024, 025, 026 dan 027. Kemudian pindahkanlah nomor register kabupaten tersebut kedalam kartu TB-01 yang sesuai. Misalkan besok anda berkunjung ke Puskesmas Sumuran dan terdapat 3 penderita TB yang diobati tapi belum terdaftar. Kerjakanlah hal yang sama. Catatlah pada
xli
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Nama lengkap Jenis kelamin Umur Alamat Lengkap Nama Unit Pengobatan Tanggal Mulai Berobat Rejimen Yang Diberikan Klasifikasi Penyakit Tipe Penderita
: : : : : : : : :
Pemeriksaan Dahak
Tanggal Berhenti Berobat : Keterangan :
buku register kabupaten TB-03, no. Reg. TB. Kab. nya dengan nomor 028, 029 dan 030 sebagai kelanjutan dari nomor terakhir pada puskesmas sebelumnya. Kemudian pindahkanlah nomer register tersebut kedalam kartu pengobatan TB-01 yang sesuai. Tulis nama lengkap. Tulis L untuk laki-laki, dan P untuk perempuan. Tulis umur penderita dalam tahun. Tulis alamat lengkap. Tulis namanya, misalnya Puskesmas Waringin. Tulis tanggal penderita tersebut mulai berobat sesuai kartu pengobatan (TB.01). Tulis Kat.1, atau Kat.2 atau Kat.3 sesuai paduan pengobatan yang diberikan. Tulis P untuk penderita TB Paru; tulis EP untuk Ekstra Paru. Tulis pada kolom yang sesuai dengan tipe penderita dengan huruf B untuk penderita Baru, K untuk penderita Kambuh, P untuk penderita Pindahan, D untuk penderita Defaulter dan G untuk penderita Gagal (dalam kolom Lain-lain). Yang ditulis hanya salah satu saja, yang lain dikosongkan. Tulis nomor Register Laboratorium dan hasilnya pada kolom yang sesuai. Tulis tanggal pada kolom yang sesuai (hanya salah satu kolom yang ditulis, yang lain dikosongkan). Tulis keterangan lain yang dianggap masih perlu.
Formulir TB.04 (Register Laboratorium TBC): Buku ini untuk mencatat setiap melakukan pemeriksaan dahak dari seorang penderita (baik untuk penderita suspek maupun untuk follow-up pengobatan). Buku ini diisi oleh petugas laboratorium yang melakukan pewarnaan dan pembacaan sediaan dahak di UPK. Nomor Identitas Sediaan : Tulis sesuai dengan nomor yang ada pada kaca sediaan yang diperiksa. Nomor Reg. Lab : Tulis nomor register Lab. dengan 3 digit, mulai dengan 001 pada setiap permulaan tahun anggaran dan tulis berurutan berdasarkan tanggal pemeriksaan. Tanggal Pemeriksaan : Tulis tanggal pemeriksaan sediaan dahak tersebut. Nama Lengkap Penderita : Tulis nama lengkap.
xlii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Umur L / P
: Tulis umur dalam tahun pada kolom jenis kelamin yang sesuai. Alamat : Tulis alamat lengkap. Nama Unit Pengobatan : Tulis nama unit pengobatan yang meminta dilakukannya pemeriksaan laboratorium ini. Alasan pemeriksaan : Bila alasan pemeriksaan dahak untuk diagnosa, beri tanda rumput ( ) kolom diagnosa. Bila alasan pemeriksaan dahak untuk follow-up pengobatan tulislah No. Reg. TB. Kab. penderita tersebut pada kolom follow-up (tulis nomor, bukan tanda rumput). Hasil Pemeriksaan (terdapat 3 kolom: A, B, dan C) : Tulis hasil pemeriksaan dengan lengkap sesuai dengan tingkat positifnya yaitu 1+, 2+, atau 3+ atau Neg pada kolom yang sesuai. Kolom A untuk dahak sewaktu pertama, Kolom B untuk dahak pagi, dan kolom C untuk dahak sewaktu kedua. Tanda tangan : Bubuhi tanda tangan dari petugas yang melakukan pemeriksaan. Keterangan : Disediakan untuk hal-hal lain yang diperlukan. Formulir TB.05 (Formulir Permohonan Laboratorium TBC Untuk Pemeriksaan Dahak): Formulir ini diisi: Bagian atas oleh petugas yang meminta pemeriksaan dahak Bagian bawah oleh petugas yang membaca sediaan dahak. Satu penderita menggunakan satu formulir. Satu formulir digunakan untuk 3 spesimen (untuk diagnosis) atau untuk 2 spesimen (untuk follow-up pengobatan). Cara mengisi bagian atas: Nama Unit Pengobatan Nama tersangka/penderita Umur Jenis kelamin Alamat lengkap Kabupaten/Kota Klasifikasi Penyakit Alasan pemeriksaan : Tulis nama unit pengirim. : Tulis nama lengkap dari tersangka/penderita : Tulis umur dalam tahun. : Beri tanda pada kotak yang sesuai. : Tulis alamat penderita secara lengkap. : Tulis nama kabupaten / kota. : Beri tanda pada kotak yang sesuai. : Beri tanda pada kotak yang sesuai. Bila alasan pemeriksaan adalah untuk Follow-up pengobatan, maka harus ditulis pemeriksaan tsb untuk akhir bulan ke berapa, dan tulis juga No. Reg. TB. Kab. dari penderita tsb. Hal-hal ini tidak perlu diisi kalau alasan pemeriksaan tsb untuk diagnosa.
xliii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
: Tulis sesuai dengan nomer yang ada pada kaca sediaan, dengan tidak mencantumkan waktu pengambilan dahak (SPS). Lingkari waktu pengambilan dahak yang dikirim. Tanggal pengambilan dahak : Tulis tanggal pengambilan dahak terakhir. Tanggal pengiriman dahak : Tulis tanggal sediaan tsb dikirim ke Lab. Tanda tangan pengambil spesimen : Bubuhi tanda tangan dari pengambil/pembuat sediaan. Secara visual dahak tampak : Beri tanda pada kotak yang sesuai. Cara mengisi bagian bawah: (diisi oleh petugas lab yang membaca sediaan). No. Register Lab. Tanggal pemeriksaan Hasil : Tulis nomor yang sesuai dengan di buku register lab (TB.04). : Tulis tanggal sediaan tsb diperiksa. : Tulis POS bila hasilnya BTA positif, dan tulis NEG bila hasilnya BTA negatif. Tidak boleh tulis dengan tanda ( + ) atau ( - ). : Beri tanda rumput ( ) pada kotak yang sesuai untuk tiap sediaan yang diperiksa. : Bubuhi tanda tangan dan tulis nama lengkap petugas pemeriksa.
Nomor identitas sediaan
Tingkat positif Diperiksa oleh
Formulir TB.06 (Daftar Suspek Yang Diperiksa Dahak SPS): Formulir ini merupakan buku bantu bagi petugas TB di UPK yang mengobati penderita. No. : Tulis nomor urut 3 digit, dimulai dengan 001, pada setiap permulaan tahun. No. identitas sediaan dahak : Tulis nomor urut sediaan tersebut dengan 3 digit, mulai dengan 001 setiap permulaan tahun, nomor ini sesuai dengan nomor urut pada kolom-1 Nama tersangka penderita : Tulis nama lengkap. Umur dan jenis kelamin : Tulis umur penderita dalam tahun dalam kotak yang sesuai jenis kelamin penderita tsb. Alamat lengkap : Tulis alamat lengkap penderita. Hasil pemeriksaan : Tulis tanggal dan hasil pembacaan sediaan sesuai kolomnya, neg untuk negatif dan 1+, 2+ dst. untuk hasil positif. A untuk dahak sewaktu pertama, B untuk dahak pagi, dan C untuk dahak sewaktu kedua. Nomor Reg. Lab. : Tulis No. Reg. Lab dari pemeriksaan tsb. (kutip dari form. TB.05 bagian bawah).
xliv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Formulir TB.07 (Laporan Triwulan Penemuan Kasus Baru Dan Kambuh): Laporan ini dibuat oleh petugas kabupaten / kota, sumber data dari buku register TB kabupaten (TB.03). Laporan dibuat dan dikirim ke propinsi setiap triwulan. Misalnya pada permulaan April 2000 petugas kabupaten / kota harus membuat laporan TB.07 dengan menghitung jumlah penderita yang terdaftar dalam buku register TB kabupaten (TB.03) pada 1 Januari s/d 31 Maret tahun 2000. Laporan tersebut sudah harus diterima oleh propinsi paling lambat tanggal 10 April 2000. Demikian juga untuk triwulantriwulan berikutnya. Triwulan/Tahun : Tulis triwulan berapa penderita-penderita tersebut terdaftar (sesuai dengan tahun anggaran, kemudian diperjelas lagi dengan menulis dari bulan apa sampai bulan apa). Propinsi : Tulis nama propinsi. Kabuapaten/Kota : Tulis nama kabupaten / kota. Nomor Kode Kab/Kota : Tulis nomor kode kabupaten/kota yang diberikan oleh Propinsi. Jumlah Puskesmas (UPK) : Tulis jumlah puskesmas (UPK) yang sudah DOTS melaksanakan strategi DOTS. Jumlah suspek yang diperiksa : Tulis jumlah suspek yang diperiksa dalam triwulan tersebut. Blok 1 : Hitung dan tulis jumlah masing-masing kelompok (klasifikasi/tipe) penderita pada kotak yang sesuai. L adalah singkatan untuk laki-laki, P singkatan untuk perempuan, dan T singkatan untuk total (jumlah). : Hitung dan tulis jumlah masing-masing kelompok umur dan jenis kelamin penderita. Ingat, blok 2 ini merupakan perincian dari hanya penderita baru BTA positif. Oleh karena itu, angka pada kotak L, P dan T dari kolom 1 Blok 1 harus sama dengan angka pada kotak L, P, dan jumlah pada kolom Total Blok 2.
Blok 2
Formulir TB.08 (Laporan Triwulan Hasil Pengobatan Penderita TBC Yang Terdaftar 12 15 Bulan Lalu): Laporan ini dibuat oleh petugas kabupaten/kota. Sumber data berasal dari buku register TB kabupaten (TB.03). Laporan dibuat pada setiap permulaan triwulan untuk melaporkan bagaimana hasil pengobatan kelompok penderita yang terdaftar dalam buku register TB kabupaten pada 12-15 bulan yang lalu. Misalnya pada permulaan April 2000, petugas kabupaten/kota melaporkan hasil pengobatan penderita-penderita yang terdaftar pada 1
xlv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Januari s/d 31 Maret 1999. Laporan sudah harus diterima oleh propinsi paling lambat tanggal 10 April 2000. Demikian juga untuk triwulan-triwulan berikutnya. Kab/Kota, Nomor Kode Kab/Kota, Nama Wasor Triwulan/tahun Jumlah penderita TB Paru yang terdaftar dalam triwulan tersebut untuk diobati : Jelas cara pengisiannya. : Tulis triwulan dan tahun laporan dibuat. Kemudian tulis bulan apa sampai bulan apa triwulan tersebut. : Tulis jumlah penderita sesuai jenis kelamin dan tipe penderita. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang pernah dilaporkan dalam TB.07 pada 12 bulan yang lalu. : Tulis berapa penderita yang terdaftar dalam triwulan tersebut yang dinyatakan sembuh. : Tulis berapa penderita yang dinyatakan Pengobatan Lengkap. : Tulis jumlah penderita yang meninggal oleh segala sebab. : Tulis jumlah penderita yang pindah berobat ke kabupaten lain dan hasil akhir peng-obatannya tidak diketahui. : Tulis jumlah penderita yang dinyatakan default / D.O (putus berobat lebih dari 2 bulan berturut). : Tulis jumlah penderita yang dinyatakan gagal (BTA yang masih tetap / kembali jadi positif pada akhir bulan ke 5 atau lebih). : Tulis jumlah penderita kolom 5 s/d 10.
Sembuh (BTA Neg) Pengobatan Lengkap Meninggal Pindah ke Kabupaten lain
Default / D.O Gagal Jumlah penderita yang dievaluasi
Formulir TB.09 (Formulir Rujukan / Pindah Penderita TBC): Formulir ini digunakan bila ada seorang penderita akan dirujuk atau pindah berobat ke UPK diluar wilayah kabupaten / kota. Formulir ini perlu untuk UPK yang baru, sehingga pengobatan dapat dilanjutkan dengan mudah. Bagian atas dari formulir ini diisi oleh petugas dari unit pengobatan yang mengirim penderita. Bagian bawah formulir diisi oleh petugas yang menerima rujukan / pindahan penderita, kemudian dikirim balik ke unit pengirim sehingga petugas pengirim tahu bahwa penderita tersebut sudah meneruskan pengobatannya. Cara pengisian dari formulir ini cukup jelas (tidak perlu diberikan petunjuk tambahan).
xlvi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Formulir TB.10 (Formulir Hasil Akhir Pengobatan Dari Pindahan):
Penderita TBC
Formulir ini diisi oleh unit pengobatan yang menerima penderita pindahan. Formulir ini diisi setelah hasil akhir pengobatan penderita pindahan tersebut diketahui, misalnya: sembuh, pengobatan lengkap, meninggal, default, gagal atau pindah ke unit lain lagi. Formulir TB.10 dikirim ke unit pengobatan dimana penderita tersebut terdaftar pertama kali karena hasil pengobatan penderita tersebut akan dilaporkan secara cohort (harus dilaporkan dari unit pengobatan dimana penderita terdaftar pertama kali). Formulir TB.11 (LAPORAN TRIWULAN HASIL PEMERIKSAAN DAHAK AKHIR TAHAP INTENSIF UNTUK PENDERITA TERDAFTAR 3 6 BULAN LALU): Laporan dibuat oleh petugas kabupaten/kota sumber data dari buku register TB kabupaten (TB.03). Laporan dibuat pada setiap permulaan triwulan untuk melaporkan bagaimana hasil pemeriksaan ulang dahak pada akhir tahap intensif dari kelompok penderita yang terdaftar dalam buku register TB kabupaten pada 3 6 bulan yang lalu. Misalnya pada permulaan April 2000, petugas kabupaten / kota melaporkan TB.11 dari penderita-penderita yang terdaftar pada 1 Oktober s/d 31 Desember 1999. Laporan sudah harus diterima oleh propinsi paling lambat tanggal 10 April 2000. Demikian juga untuk triwulan-triwulan berikutnya. Nama Propinsi, Kab/Kota, Nama Wasor : jelas cara pengisiannya. Triwulan/Tahun : Tulis triwulan dan tahun berapa penderita tersebut terdaftar, kemudian tulis dari bulan apa sampai bulan apa triwulan tersebut. Jumlah penderita terdaftar untuk diobati : Tulis jumlah penderita yang terdaftar dalam triwulan tersebut untuk masing-masing tipe penderita. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang pernah dilaporkan dalam TB.07 pada 3 bulan yang lalu. Jumlah penderita yang mengalami Konversi (BTA Neg) : Tulis jumlah penderita (untuk masing-masing tipe penderita) yang hasil pemeriksaan dahak ulang pada akhir tahap intensif sudah menjadi negatif. Jumlah penderita yang tidak mengalami Konversi (BTA tetap Positif) : Tulis jumlah penderita (untuk masing-masing tipe penderita) yang hasil pemeriksaan dahak ulang pada akhir tahap intensif tetap positif. Jumlah penderita yang tidak ada hasil pemeriksaan dahak : Tulis jumlah penderita (untuk masing-masing tipe penderita) yang hasil pemeriksaan dahak
xlvii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
ulangnya pada akhir tahap intensif tidak diketahui atau tidak dilakukan. Jumlah penderita meninggal, pindah, default dalam tahap intensif : Tulis jumlah penderita (untuk masing-masing tipe penderita) yang meninggal, pindah atau default dalam tahap intensif sehingga tidak berhasil diperiksa dahaknya. Jumlah yang dievaluasi : Tulis jumlah penderita pada kolom 3 + 4 + 5 + 6.
Formulir TB.12 (Formulir Pengiriman Sediaan Untuk Cross Check): Formulir ini dipakai untuk pengambilan sediaan dahak dari laboratorium pemeriksa pertama (misalnya PRM, PPM dll) untuk dikirim ke laboratorium rujukan (misalnya BLK) dengan maksud untuk di cross check. Formulir ini diisi oleh 2 petugas, yaitu: 1) Petugas yang mengambil sediaan (petugas kabupaten / kota) mengisi bagian kiri formulir, yaitu: Nama Lab. pemeriksa peretama Nama petugas Lab. pemeriksa pertama Tanggal sediaan diambil Kolom 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. (kolom 5 dan 6 hanya diisi pada lembar ke 2, lembar ke 1 untuk dikirim ke laboratorium rujukan tidak boleh diisi kolom 5 dan 6). 2) Petugas pelaksana cross check (petugas laboratorium rujukan), setelah melakukan pemeriksaan cross check, mengisi bagian kanan formulir, yaitu kolom 7 s/d 12. Kolom 7 untuk menulis tanggal pemeriksaan cross check, kolom 8 untuk menulis hasil bacaan sediaan. Kolom 9 dan 10 disediakan untuk menilai kualitas sediaan. Pengisiannya dengan cara memberi tanda pada kolom yang sesuai, yaitu B = baik dan J = jelek. Demikian juga untuk kolom 11 dan 12 disediakan untuk menilai kualitas pewarnaan. Cara pengisiannya sama seperti untuk kolom 9 dan 10, yaitu dengan memberi tanda pada kolom yang sesuai. Setelah mengisi hasil cross check, petugas laboratorium rujukan harus mengirim kembali formulir tersebut ke petugas Dinas Kesehatan kabupaten / kota untuk dianalisis hasilnya. Setelah petugas Dinas Kesehatan kabupaten/kota menerima hasil pemeriksaan cross check dari petugas laboratorium rujukan, petugas kabupaten/kota melakukan analisis dengan menghitung positif palsu, negatif palsu dan error rate dengan mengikuti petunjuk perhitungan seperti pada bagian bawah formulir TB.12. Formulir TB.13 (Laporan Penerimaan dan Pemakaian OAT di Kabupaten):
xlviii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Formulir ini diisi oleh petugas TBC kabupaten/kota dan dikirim ke Propinsi untuk monitoring persediaan Obat Anti Tuberkulosis di tingkat kabupaten/kota. Cara pengisian dari formulir ini cukup jelas (tidak perlu diberikan petunjuk tambahan).
Formulir REKAPITULASI TB.07, BLOK 1: Formulir ini diisi oleh petugas Propinsi sebagai laporan triwulan ke Pusat tentang penemuan penderita berdasarkan klasifikasi / tipe penderita dan dilaporkan per kabupaten / kota. Cara pengisian formulir ini cukup jelas, datanya diambil dari blok 1 TB.07 yang dilapor oleh kabupaten / kota. Formulir REKAPITULASI TB.07, BLOK 2: Formulir ini diisi oleh petugas Propinsi sebagai laporan triwulan ke Pusat tentang perincian berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin, yang dihitung hanya dari penderita baru BTA positif dan dilaporkan per kabupaten / kota. Cara pengisian formulir ini cukup jelas, datanya diambil dari blok 2 TB.07 yang dilapor oleh kabupaten / kota. Formulir REKAPITULASI TB.08 Per Kabupaten/Kota (Hasil Pengobatan Dari Penderita Baru BTA Positif): Formulir ini diisi oleh petugas propinsi sebagai laporan triwulan ke Pusat tentang hasil pengobatan penderita baru BTA positif yang dilaporkan per kabupaten / kota. Cara pengisian formulir ini, data diambil dari angka-angka pada baris penderita baru BTA positif laporan TB.08 kabupaten / kota. Propinsi Triwulan/tahun : Tulis nama propinsi secara lengkap. : Tulis triwulan ke berapa sesuai dengan laporan TB.08 kabupaten / kota. Triwulan tersebut dihitung berdasarkan tahun anggaran. Kemudian untuk jelasnya, tulis dari bulan apa sampai dengan bulan apa. : cukup jelas. : cukup jelas, L = laki-laki, P = perempuan, T = L + P. : cukup jelas. : (kolom 6 : kolom 5) x 100% : cukup jelas.
xlix
Kolom 1 dan 2 Kolom 3, 4 dan 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Kolom 9 : (kolom 8 : kolom 5) x 100% Kolom 10 : cukup jelas. Kolom 11 : (kolom 10 : kolom 5) x 100% Kolom 12 : cukup jelas. Kolom 13 : (kolom 12 : kolom 5) x 100% Kolom 14 : cukup jelas. Kolom 15 : (kolom 14 : kolom 5) x 100% Kolom 16 : cukup jelas. Kolom 17 : (kolom 16 : kolom 5) x 100% Kolom 18 : kolom 6 + 8 + 10 + 12 + 14 +16. Kolom 19 : (kolom 18 : kolom 5) x 100%. Formulir REKAPITULASI TB.08 Per Kabupaten/Kota (Hasil Akhir Pengobatan Penderita Kambuh): Maksud dan cara pengisian formulir ini pada prinsipnya sama dengan formulir rekapitulasi TB.08 dari penderita baru tersebut diatas. Formulir REKAPITULASI TB.08 Per Kabupaten/Kota (Hasil Pengobatan Penderita Baru BTA Negatif Rontgen Positif): Maksud dan cara pengisian formulir ini pada prinsipnya sama dengan formulir rekapitulasi TB.08 penderita baru tersebut diatas.
Formulir REKAPITULASI TB. 11 Per Kabupaten/Kota (Penderita Baru BTA Positif):
Formulir ini diisi oleh petugas TB propinsi, sebagai laporan triwulan ke Pusat, tentang hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif untuk penderita TB paru terdaftar 3 - 6 bulan yang lalu. Formulir ini diisi dengan data laporan TB.11, kolom 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, masing-masing kabupaten/ kota. Setiap tipe penderita di rekapitulasi secara tersendiri. Sehingga akan ada rekapitulasi pemeriksaan dahak akhir tahap intensif penderita BTA postif baru, kambuh dan gagal. Cara pengisisan formulor rekapitilasi TB.11 adalah sebagai berikut: 1) Rekapitulasi TB. 11 Penderita BTA Positif Baru Untuk mengisi, ambilah data laporan TB. 11masing-masing kabupaten/ kota, khusus untuk hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif penderita BTA positif baru. a) Propinsi: Tulis nama propinsi secara lengkap dan jelas. b) Triwulan/ tahun: Tulis triwulan ke berapa sesuai dengan laporan TB.11 kabupaten/ kota. Triwulan dihitung berdasar tahun anggaran. Kemudian tulis bulan triwulan yang bersangkutan, dari bulan apa sampai dengan bulan apa. c) Kolom 1 & 2: Tulis nomer urut serta nama kabupaten/ kota yang bersangkutan. d) Kolom-3: Tulis jumlah penderita BTA positif baru yang terdaftar dan diobati dari masing-masing kabupaten/ kota yang bersangkutan.
l
Program Penanggulangan Tuberkulosis
e) Kolom-4: Tulis jumlah penderita BTA positif baru yang diperiksa dahaknya pada akhir tahap intensif dan mengalami konversi, BTA positif menjadi BTA negatif. dari masing-masing kabupaten/ kota. f) Kolom-5: Tulis prosentasi jumlah penderita BTA positif baru yang konversi menjadi BTA negatif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif baru yang terdaftar dan diobati. dari masing-masing kabupaten/ kota. g) Kolom-6: Tulis jumlah penderita BTA positif baru yang diperiksa dahaknya pada akhir tahap intensif, tetapi tidak mengalami konversi menjadi BTA negatif. dari masing-masing kabupaten/ kota. h) Kolom-7: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif baru yang tidak mengalami konversi, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif baru yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. i) Kolom-8: Tulis jumlah penderita BTA positif baru yang tidak ada hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif, dari masing-masing kabupaten/ kota. j) Kolom-9: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif baru yang tidak ada hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif baru yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. k) Kolom-10: Tulis seluruh jumlah penderita BTA positif baru yang meninggal, pindah dan default selama tahap intensif, dari masing-masing kabupaten/ kota. l) Kolom-11: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif baru yang meninggal, pindah dan default selama tahap intensif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif baru yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. m) Kolom-12: Tulis seluruh jumlah penderita BTA positif baru yang dievaluasi selama tahap intensif (kolom 4 + 6 + 8 + 10), dari masing-masing kabupaten/ kota. n) Kolom-13: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif baru yang dievaluasi selama tahap intensif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif baru yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. o) Tulis nama kota dan tanggal dimana & kapan laporan rekapitulasi TB.11 dibuat. p) Pembuat laporan: Tulis tanda tangan pembuat laporan, nama terang dan NIP. q) Mengetahui: Tulis tanda tangan, nama terang dan NIP atasan langsung pembuat laporan. 2) Rekapitulasi TB. 11 Penderita BTA Positif Kambuh Untuk mengisi, ambilah data laporan TB. 11masing-masing kabupaten/ kota, khusus untuk hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif penderita BTA positif kambuh. a. Propinsi: Tulis nama propinsi secara lengkap dan jelas. b. Triwulan/ tahun: Tulis triwulan ke berapa sesuai dengan laporan TB. 11kabupaten/ kota. Triwulan dihitung berdasar tahun anggaran. Kemudian tulis bulan triwulan yang bersangkutan, dari bulan apa sampai dengan bulan apa. c. Kolom 1 & 2: Tulis nomer urut serta nama kabupaten/ kota yang bersangkutan. d. Kolom-3: Tulis jumlah penderita BTA positif kambuh yang terdaftar dan diobati dari masing-masing kabupaten/ kota yang bersangkutan. e. Kolom-4: Tulis jumlah penderita BTA positif kambuh yang diperiksa dahaknya pada akhir tahap intensif dan mengalami konversi, BTA positif menjadi BTA negatif. masing-masing kabupaten/ kota.
li
Program Penanggulangan Tuberkulosis
f. Kolom-5: Tulis prosentasi jumlah penderita BTA positif kambuh yang konversi menjadi BTA negatif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif kambuh yang terdaftar dan diobati masing-masing kabupaten/ kota. g. Kolom-6: Tulis jumlah penderita BTA positif kambuh yang diperiksa dahaknya pada akhir tahap intensif, tetapi tidak mengalami konversi menjadi BTA negatif. masingmasing kabupaten/ kota. h. Kolom-7: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif kambuh yang tidak mengalami konversi, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif kambuh yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. i. Kolom-8: Tulis jumlah penderita BTA positif kambuh yang tidak ada hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif, dari masing-masing kabupaten/ kota. j. Kolom-9: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif kambuh yang tidak ada hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif kambuh yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. k. Kolom-10: Tulis seluruh jumlah penderita BTA positif kambuh yang meninggal, pindah dan default selama tahap intensif, dari masing-masing kabupaten/ kota. l. Kolom-11: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif kambuh yang meninggal, pindah dan default selama tahap intensif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif kambuh yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. m. Kolom-12: Tulis seluruh jumhlah penderita BTA positif kambuh yang dievaluasi selama tahap intensif (kolom 4 + 6 + 8 + 10), dari masing-masing kabupaten/ kota. n. Kolom-13: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif kambuh yang dievaluasi selama tahap intensif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif kambuh yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. o. Tulis nama kota dan tanggal dimana & kapan laporan rekapitulasi TB. 11dibuat. p. Pembuat laporan: Tulis tanda tangan pembuat laporan, nama terang dan NIP. q. Mengetahui: Tulis tanda tangan, nama terang dan NIP atasan langsung pembuat laporan. 3) Rekapitulasi TB. 11 Penderita BTA Positif Gagal. Untuk mengisi, ambilah data laporan TB. 11masing-masing kabupaten/ kota, khusus untuk hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif penderita BTA positif gagal. a. Propinsi: Tulis nama propinsi secara lengkap dan jelas. b. Triwulan/ tahun: Tulis triwulan ke berapa sesuai dengan laporan TB. 11kabupaten/ kota. Triwulan dihitung berdasar tahun anggaran. Kemudian tulis bulan triwulan yang bersangkutan, dari bulan apa sampai dengan bulan apa. c. Kolom 1 & 2: Tulis nomer urut serta nama kabupaten/ kota yang bersangkutan. d. Kolom-3: Tulis jumlah penderita BTA positif gagal yang terdaftar dan diobati dari masing-masing kabupaten/ kota yang bersangkutan. e. Kolom-4: Tulis jumlah penderita BTA positif gagal yang diperiksa dahaknya pada akhir tahap intensif dan mengalami konversi, BTA positif menjadi BTA negatif. dari masing-masing kabupaten/ kota. f. Kolom-5: Tulis prosentasi jumlah penderita BTA positif gagal yang konversi menjadi BTA negatif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif gagal yang terdaftar dan diobati. dari masing-masing kabupaten/ kota.
lii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
g. Kolom-6: Tulis jumlah penderita BTA positif gagal yang diperiksa dahaknya pada akhir tahap intensif, tetapi tidak mengalami konversi menjadi BTA negatif. dari masing-masing kabupaten/ kota. h. Kolom-7: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif gagal yang tidak mengalami konversi, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif gagal yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. i. Kolom-8: Tulis jumlah penderita BTA positif gagal yang tidak ada hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif, dari masing-masing kabupaten/ kota. j. Kolom-9: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif gagal yang tidak ada hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif gagal yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. k. Kolom-10: Tulis seluruh jumlah penderita BTA positif gagal yang meninggal, pindah dan default selama tahap intensif, dari masing-masing kabupaten/ kota. l. Kolom-11: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif gagal yang meninggal, pindah dan default selama tahap intensif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif gagal yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. m. Kolom-12: Tulis seluruh jumlah penderita BTA positif gagal yang dievaluasi selama tahap intensif (kolom 4 + 6 + 8 + 10), dari masing-masing kabupaten/ kota. n. Kolom-13: Tulis prosentasi jumlah pendertita BTA positif gagal yang dievaluasi selama tahap intensif, terhadap seluruh jumlah penderita BTA positif gagal yang terdaftar dan diobati, dari masing-masing kabupaten/ kota. o. Tulis nama kota dan tanggal dimana & kapan laporan rekapitulasi TB. 11dibuat. p. Pembuat laporan: Tulis tanda tangan pembuat laporan, nama terang dan NIP. q. Mengetahui: Tulis tanda tangan, nama terang dan NIP atasan langsung pembuat laporan. Formulir REKAPITULASI TB.12 KABUPATEN: Formulir ini diisi oleh petugas kabupaten / kota berdasarkan analisa hasil cross check (Formulir TB.12 bagian bawah). Hasil penilaian kualitas sediaan maupun kualitas pewarnaan, dianalisa per laboratorium pemeriksa pertama (misalnya PRM, PPM, dll). Rekapitulasi TB.12 kabupaten digunakan sebagai umpan balik ke laboratorium pemeriksa pertama dan laboratorium rujukan; juga sebagai laporan ke Propinsi. Triwulan/Tahun Kabupaten/Kota Jumlah seluruh Lab. Pemeriksa Pertama Nama Lab. Pemeriksa Pertama Kolom 3 Kolom 4, 5 dan 6 : Tulis triwulan ke berapa cross check ini dilaksanakan. : Tulis nama k abupaten / kota. : cukup jelas. : Tulis semua nama Lab. Pemeriksa Pertama pada baris-baris yang tersedia, bila tidak cukup gunakan halaman lain. : cukup jelas. : dikutip dari bagian bawah formulir TB12 (analisa hasil cross check).
liii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Kolom 7
Kolom 8
: Tulis berapa % sediaan dengan kualitas jelek. Angka ini didapat dari jumlah sediaan dengan kualitas jelek dibagi jumlah seluruh sediaan yang di cross check dikali 100% : Tulis berapa % sediaan yang kualitas pewarnaan jelek. Angka ini didapat dari jumlah sediaan dengan kualitas pewarnaan jelek dibagi jumlah seluruh sediaan yang di cross check dikali 100%.
Untuk Laboratorium Pemeriksa Pertama yang tidak dilakukan cross check, kolom 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dibiarkan kosong; dengan demikian dapat dengan mudah diketahui Laboratorium Pemeriksa Pertama mana yang tidak dilakukan pemeriksaan cross check dalam triwulan tersebut (seharusnya semua Lab. Pemeriksa Pertama dilakukan pemeriksaan cross check). Formulir REKAPITULASI FORMULIR TB.12 PROPINSI: Formulir ini diisi oleh petugas Dinas Kesehatan propinsi dan dilaporkan ke Pusat bersama Rekapitulasi TB.07, TB.08, dan TB.11. Pengisian formulir ini berdasarkan data dari Formulir Rekapitulasi TB.12 kabupaten. Cara pengisiannya adalah per kabupaten / kota. Kolom 1, 2 dan 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 : cukup jelas. : Tulis jumlah Lab. Pemeriksa Pertama yang dilakukan cross check. : (kolom 4 : kolom 3) x 100% : Tulis jumlah Laboratorium Pemeriksa Pertama yang error rate nya (berdasarkan analisis hasil cross check) lebih kecil atau sama dengan 5%. : (kolom 6 : kolom 3) x 100% : Tulis rentang error rate (yang terendah yang tertinggi)
Formulir REKAPITULASI FORMULIR TB. 13 PROPINSI: Formulir ini diisi oleh petugas Dinas Kesehatan propinsi dan dilaporkan ke Pusat bersama rekapitulasi TB. 07, TB. 08 dan TB. 11. Pengisian formulir ini berdasarkan data laporan TB. 13 masing-masing kabupaten/ kota di wilayah propinsi yang bersangkutan. Cara pengisian formulir rekapitulasi TB. 13 adalah sebagai berikut: 1. Propinsi: Tulis nama propinsi secara lengkap dan jelas.
liv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
2. Triwulan/ tahun: Tulis triwulan ke berapa sesuai dengan laporan TB.11 kabupaten/ kota. Triwulan dihitung berdasar tahun anggaran. Kemudian tulis bulan triwulan yang bersangkutan, dari bulan apa sampai dengan bulan apa. 3. Kolom-1 & 2: Tulis nomer urut serta nama kabupaten/ kota yang bersangkutan. 4. Kolom-3: Tulis stok akhir OAT kategori-1 pada akhir triwulan. serta tanggal kedaluarsa sesuai barisnya. 5. Kolom-4: Tulis stok akhir OAT kategori-2 pada akhir triwulan. serta tanggal kedaluarsa sesuai barisnya. 6. Kolom-5: Tulis stok akhir OAT kategori-3 pada akhir triwulan. serta tanggal kedaluarsa sesuai barisnya. 7. Kolom-6: Tulis stok akhir OAT kategori-anak pada akhir triwulan. serta tanggal kedaluarsa sesuai barisnya. 8. Kolom-7: Tulis stok akhir OAT kategori-sisipan pada akhir triwulan. serta tanggal kedaluarsa sesuai barisnya. Tulis nama kota dan tanggal dimana & kapan laporan rekapitulasi TB. 13 dibuat. Pembuat laporan: Tulis tanda tangan pembuat laporan, nama terang dan NIP. Mengetahui: Tulis tanda tangan, nama terang dan NIP atasan langsung pembuat laporan.
lv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Bagan-4 Alur Pengumpulan Data dan Umpan Balik Penanggulangan Tuberkulosis
PUSAT
PROPINSI (Dinas Kesehatan)
Reka p
Reka p
Reka p
Rekap TB.12 Propinsi
TB.13
TB.07
TB.08
TB. 11
Rekap TB12
Kabupate KABUPATEN/KOTA (Dinas Kesehatan)
TB. 03
TB. 12
TB. 13
UNIT PELAYANAN KESEHATAN (UPK) (Puskesmas,RS,RSTP,
TB. 01
TB 01 TB 01 TB 01
Keterangan: = Pengambilan Data = Data diolah menjadi = Alur Laporan = Alur Umpan Balik lvi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
lvii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
BAB X SUPERVISI
Supervisi merupakan salah satu kegiatan pokok dari manajemen. Kegiatan supervisi ini erat hubungannya dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Supervisi dapat dikatakan sebagai monitoring langsung, sedangkan monitoring dapat dikatakan sebagai supervisi tidak langsung. 1. TUJUAN SUPERVISI Tujuan supervisi untuk meningkatkan kinerja petugas, melalui suatu proses yang sistematis dengan : 1.1. Peningkatan pengetahuan petugas. 1.2. Peningkatan ketrampilan petugas. 1.3. Perbaikan sikap petugas dalam bekerja. 1.4. Peningkatan motivasi petugas. Supervisi selain merupakan monitoring langsung, juga merupakan kegiatan lanjutan pelatihan. Melalui supervisi dapat diketahui bagaimana petugas yang sudah dilatih tersebut menerapkan semua pengetahuan dan ketrampilannya. Selain itu supervisi dapat juga berupa suatu proses pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam bentuk on the job training. Supervisi harus dilaksanakan di semua tingkat dan disemua unit pelaksana, karena dimanapun petugas bekerja akan tetap memerlukan bantuan untuk mengatasi masalah dan kesulitan yang mereka temukan. Suatu umpan balik tentang penanpilan kerja mereka harus selalu diberikan untuk memberikan dorongan semangat kerja. 2. PELAKSANAAN SUPERVISI. 2.1. Supervisi harus dilaksnakan secara rutin, teratur dan terencana. a. Supervisi ke UPK (misalnya Puskesmas, RS, BP4, termasuk laboratorium) harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. b. Supervisi ke daerah kabupaten / kota dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. c. Supervisi ke daerah propinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. 2.2. Pada keadaan tertentu frekuensi supervisi perlu ditingkatkan. Frekuensi supervisi perlu ditingkatkan:
lviii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
a. Pada tahap awal pelaksanaan program. b. Bila kinerja dari suatu unit kurang baik, misalnya angka konversi rendah, angka kesembuhan (cure rate) rendah, atau jumlah suspek yang diperiksa dan jumlah penderita TBC yang diobati terlalu sedikit dari yang diharapkan. 2.3. Keberhasilan supervisi. Keberhasilan Supervisi tergantung pada: a. Kepribadian pelaksana supervisi atau supervisor. Penyelia (Supervisor) harus mempunyai kepribadian yang menyenangkan dan bersahabat. Dapat membina hubungan baik dengan petugas di unit yang dikunjungi. Supervisor harus mendengar dengan tulus semua masalah yang disampaikan, dan bersama-sama petugas setempat mencari pemecahan. b. Persiapan supervisi. Rencana supervisi disusun setiap tahun dengan jadwal kunjungan tiap triwulan atau semester. Sebelum melakukan kunjungan, penyelia harus mereview data pendukung, laporan, korespondensi, dan temuan-temuan pada supervisi sebelumnya termasuk tindak lanjutnya. Daerah yang akan di kunjungi perlu diberi tahu sebelumnya. Kunjungan supervisi tanpa pemberitahuan sebelumnya memberi kesan sidak (inspeksi-mendadak) yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan supervisi, 3. HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM SUPERVISI. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada supervisi ditulis dalam suatu daftar tilik atau checklist supervisi. Daftar tilik minimal harus memuat kegiatan pelaksanaan program TBC. Sumber daya. Kegiatan penanggulangan TBC, yang meliputi: penemuan penderita, pengobatan, laboaratorium termasuk cross check, dan pencatatan & pelaporan . Ringkasan masalah yang ditemukan, saran pemecahan dan rencana tindak lanjut, Kegiatan lain dalam meningkatkan pelaksanaan program penanggulangan TBC. Dengan checklist, penyelia dipandu untuk bekerja secara sistematis sehingga tidak ada hal-hal penting yang luput dari perhatian. Contoh checklist supervisi untuk tiap tingkat dan unit pelayanan kesehatan dapat dilihat pada halaman berikut. Dalam pelaksanaan dilapangan, supervisor dapat memilih hal-hal mana (yang terdapat dalam contoh checklist tersebut) yang merupakan prioritas untuk di supervisi sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah masing-masing.
4. PEMECAHAN MASALAH SUPERVISI Dalam kunjungan supervisi, penyelia dapat menemukan beberapa masalah atau kesalahan, misalnya pemeriksaan dahak ulang tidak dikerjakan, hasil pemeriksaan dahak ulang dicatat pada kolom yang salah, tidak melakukan cross check, dll. Penyelia
lix
Program Penanggulangan Tuberkulosis
bersama-sama petugas yang dikunjungi mendiskusikan permasalahan tersebut serta bersama-sama mencari alternatif pemecahannya. Setelah itu, mintalah petugas melakukan sendiri dibawah bimbingan penyelia. Dengan cara on the job training, maka pengetahuan dan ketrampilan petugas diharapkan dapat segera diatasi dan diperbaiki. Bila masih ada masalah yang belum terpecahkan, maka penyelia bersama petugas dan pimpinan unit kerja menyusun Rencana Kegiatan Tindak Lanjut (RKTL) untuk pemecahan masalah tersebut. Kesimpulan dan saran pemecahan masalah harus ditulis dalam laporan supervisi sebagai dokumen untuk disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang dikunjungi dan pimpinan unit kerja terkait. 5. LAPORAN SUPERVISI Penyelia harus membuat laporan supervisi segera setelah menyelesaikan kunjungan. Laporan supervisi tersebut harus memuat paling sedikit: a. Tujuan supervisi. b. Temuan-temuan: keberhasilan dan kekurangan. c. Kemungkinan penyebab masalah atau kesalahan. d. Saran pemecahan masalah e. RKTL = Rencana Kerja Tindak Lanjut. f. Laporan supervisi: - Lembar 1 : harus diumpanbalikkan ke unit yang dikunjungi sebagai dokumen untuk bahan acuan perbaikan kegiatan. - Lembar 2 : disampaikan kepada atasan langsung penyelia sebagai bahan untuk rencana kunjungan berikutnya. - Lembar 3 : arsip penyelia.
lx
Program Penanggulangan Tuberkulosis
6. CONTOH MATERI SUPERVISI
6.1. Contoh Materi Supervisi Ke Unit Pelayanan Kesehatan
DAFTAR TILIK SUPERVISI PROGRAM PENANGGULANGAN TBC KE UNIT PELAYANAN KESEHATAN
Kabupaten/kota Tanggal kunjungan Unit Kesehatan yang di kunjungi Nama petugas yang di supervisi Jabatan : : : : : ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
1. Sumber Daya Manusia: a) Tulis nama-nama petugas yang bekerja dalam penanggulangan TBC di unit tsb. b) Siapa yang sudah dan siapa yang belum mendapat pelatihan TBC. Rencanakan pelatihan atau on the job training pada petugas yang belum mendapat pelatihan. 2. Review kegiatan bersama petugas: a) Penemuan penderita: Berapa jumlah suspek yang diperiksa dalam 3 bulan terakhir (lihat buku daftar suspek TB.06)? Berapa jumlah penderita TBC BTA Positif diantara suspek yang diperiksa dalam 3 bulan terakhir? Bandingkan jumlah suspek yang diperiksa dengan jumlah penderita TBC BTA Positif yang ditemukan Berapa jumlah penderita TBC BTA Negatif / Rontgen Positif dan TBC Ekstra Paru yang ditemukan dalam 3 bulan terakhir? Bandingkan jumlah penderita TBC BTA Positif dengan jumlah penderita BTA Negatif dan TBC Ekstra Paru Bila ditemukan masalah atau hasil kegiatannya tidak seperti yang diharapkan, diskusikan hal tersebut dengan petugas apa kemungkinan penyebab masalah dan bagaimana menyelesaikannya. b) Pengobatan penderita: Apakah semua penderita yang ditemukan sudah dapat pengobatan? Apakah semua penderita yang diobati (termasuk penderita BTA Neg/Ro Pos dan Ekstra Paru) mempunyai kartu penderita (TB.01)? Apakah jenis kategori obat yang diberikan sesuai dengan klasifikasi dan tipe penderita? Bagaimana cara pemberian obat dalam tahap intensif dan dalam tahap lanjutan (setiap hari/tiap 3hari/tiap minggu/tiap bulan)? Apakah penderita menelan obat di unit pelayanan dengan pengawasan langsung petugas?
lxi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Apakah untuk setiap penderita telah ditunjuk seorang PMO. Apakah PMO telah diberi penyuluhan? Apakah pemeriksaan dahak ulang untuk memantau kemajuan pengobatan dilaksanakan sesuai protap (yaitu pada akhir tahap intensif, pada 1 bulan sebelum akhir pengobatan dan pada akhir pengobatan)? Apakah ada penderita yang mangkir (tidak mengambil obat) yang belum dilacak? Berapa jumlah penderita Baru BTA Positif yang mulai pengobatan dalam periode 3 6 bulan yang lalu. Berapa persen diantaranya yang mengalami konversi? Berapa jumlah penderita Baru BTA Positif yang mulai pengobatan dalam periode 6 9 bulan yang lalu. Berapa persen diantaranya yang sembuh? Periksa sisa obat dari penderita yang sementara dalam pengobatan. Ambil secara acak beberapa (misalnya 2) kartu penderita yang sementara dalam pengobatan, kemudian hitung sisa obat yang terdapat dalam dos paket obat penderita tersebut, apakah sisanya sesuai dengan catatan pada kartu penderita. Bila ditemukan masalah atau hasil kegiatannya tidak seperti yang diharapkan, diskusikan hal tersebut dengan petugas apa kemungkinan penyebab masalah dan bagaimana menyelesaikannya.
3. Catat dan lengkapi Buku Register TBC Kabupaten (TB.03) yang saudara bawa, dengan data yang berasal dari kartu-kartu penderita yang telah diteliti lebih dahulu. Jangan lupa memberi nomor Register Kabupaten pada setiap kartu penderita. 4. Periksa persediaan obat dan bahan-bahan pelengkap untuk unit pelayanan penderita: a) Berapa jumlah persedian obat, apakah jumlahnya cukup, apakah ada obat yang sudah atau hampir kadaluarsa? b) Apakah pot dahak, kaca sediaan, kartu penderita dan formulir-formulir lainya jumlahnya cukup? 5. Khusus untuk unit pelayanan yang melakukan pemeriksaan mikroskopis: a) Apakah Buku Register Laboratorium (TB.04) diisi dengan lengkap dan benar? Berapa jumlah suspek yang diperiksa dalam 3 bulan terakhir? b) Berapa jumlah pemeriksaan follow-up pengobatan dalam 3 bulan terakhir? c) Apakah semua penderita BTA (+) yang ada dalam Buku Register Laboratorium (TB.04) sudah tercatat dalam Buku Register TBC Kabupaten (TB.03). Kalau belum, supaya nama penderita tersebut dicatat pada catatan khusus untuk dicek ke unit pelayanan yang bersangkutan? d) Apakah semua hasil pemeriksaan sediaan sudah dikirim kembali ke unit yang memintanya? e) Reagens (cairan pewarna): Apakah persediaan reagens cukup Apakah reagens tersebut belum kadaluarsa? (tanggal pembuatan reagens yang tercatat pada label belum lebih dari 6 bulan). f) Mikroskop: Apakah menggunakan mikroskop binokuler atau monokuler? Apakah penyimpanan mikroskop sesuai petunjuk? (bebas debu, bebas getaran dan ditempat kering).
lxii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Bagaimana kondisi mikroskop? (baik, berjamur atau rusak). g) Pengambilan sediaan untuk di crosscheck: Apakah slide positif dan slide negatif disimpan dalam kotak tersendiri? Ambil slide untuk di cross check sesuai petunjuk, yaitu seluruh slide positif dan 10% (secara acak) slide negatif, dengan ketentuan 1 slide untuk tiap penderita. Isi formulir Pengiriman Sediaan Untuk Cross Check (TBC.12). h) Bagaimana cara pembuangan limba laboratorium? 6. Ringkasan masalah-masalah yang ditemukan: 7. Saran pemecahan masalah: 8. Rencana Tindak Lanjut (Siapa, kapan dan dimana pemecahan masalah tersebut akan dilaksanakan): ., tgl.. Mengetahui: Kepala Unit Yang disupervisi Pelaksana supervisi:
(...)
()
lxiii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
6.2. Contoh Materi Supervisi Di Daerah Kabupaten / Kota
DAFTAR TILIK SUPERVISI PROGRAM PENANGGULANGAN TBC KE KABUPATEN/KOTA
Propinsi Tanggal kunjungan : ........................................................................... : ...........................................................................
Nama Kab/kota yang di kunjungi :
Nama petugas yang di supervisi Jabatan : ........................................................................... : ...........................................................................
1. Sumber Daya Manusia: a) Tulis nama-nama petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC. b) Kapan terakhir petugas-petugas tersebut mendapat pelatihan. c) Rencanakan pelatihan bagi yang belum dilatih atau yang perlu penyegaran. 2. Buku Register TBC Kabupaten: Periksa apakah buku tersebut diisi secara lengkap dan benar. Bila terdapat salah, jelaskan bagaimana yang benar dan mintalah petugas kabupaten melakukan perbaikan dibawah bimbingan supervisor. 3. Pelaporan:
lxiv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
a) Apakah laporan triwulan (TB.07, TB.08 dan TB.11) yang seharusnya sudah diselesaikan sudah dikirim ke propinsi? b) Periksa arsip laporan yang ada! c) Apakah pengisian laporan-laporan tersebut benar? d) Apakah mengirim sediaan untuk cross check (TB-12) ke BLK? e) Apakah ada hasil cross check dari BLK? 4. Review bersama petugas kabupaten bagaimana hasil pelaksanaan kegiatan penemuan penderita dan kegiatan pengobatan penderita: a) Berapa proporsi penderita baru TBC BTA Positif diantara seluruh suspek yang diperiksa (dihitung dari laporan TB.07)? b) Berapa proporsi semua penderita BTA Positif diantara semua penderita yang ditemukan (dihitung dari laporan TB.07)? c) Berapa angka kesembuhan (cure-rate), dihitung dari laporan TB.08? d) Berapa angka konversi, dihitung dari laporan TB.11? e) Berapa cakupan penemuan penderita baru TBC BTA Positif per 100.000 penduduk? f) Berapa error rate (angka kesalahan baca sediaan) dari masing-masing PRM? (berdasarkan hasil cross check/lihat Form Rekap TB.12 Kabupaten) g) Apakah analisa hasil croos check telah diumpan balikkan kepada Pusat rujukan Mikroskopis? 5. Diskusikan dengan petugas kabupaten tentang rencana pengembangan cakupan unit pelayanan didasarkan pada hasil review seperti pada butir 4 diatas: a) Puskesmas: Jumlah Puskesmas yang ada di kabupaten = buah, Yang sudah melaksanakan strategi DOTS = buah, Rencana pengembangan sebagai berikut: b) RS, BP4, Klinik, dll (Pemerintah dan Swasta): Jumlah semua yang ada = buah, Yang sudah melaksanakan strategi DOTS = buah, Rencana pengembangan sebagai berikut: 6. Supervisi petugas kabupaten ke Unit Pelayanan Kesehatan (UPK). a) Apakah kabupaten punya rencana supervisi ke UPK dan telah disampaikan ke UPK? b) Bagaimana frekwensi supervisi tersebut? c) Apakah kunjungan supervisi dilakukan sesuai dengan rencana? Berapa % rencana supervisi dapat berhasil dilaksanakan? d) Siapa yang melaksanakan supervisi? (lihat arsipnya). e) Apakah menggunakan supervisi checklist? (lihat arsipnya)
lxv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
f) Apakah dilakukan pengambilan sampel sediaan dari PRM sesuai protap? g) Apakah laporan hasil supervisi dikirim (umpan-balik) ke UPK yang disupervisi? (lihat arsip surat pengantar). h) Apakah masalah yang ditemukan sudah di tindak-lanjuti? 7. Persediaan Obat dan Bahan-Bahan Pelengkap a) Bagaimana proses perencanaan untuk pengadaan obat/bahan-bahan tersebut? b) Bagaimana persediaan bahan-bahan pelengkap? (formulir, pot dahak, kaca sediaan, reagensia, dll). c) Periksa persediaan obat dengan mengunjungi GFK (Gudang Farmasi Kabupaten). 8. Kunjungan ke Gudang Farmasi Kabupaten: a) Bagaimana cara penyimpanan obat? b) Berapa jumlah persediaan obat Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3 dan Sisipan. c) Kapan tanggal kadaluarsa dari obat-obat tersebut? Apakah ada obat yang sudah kadaluarsa? d) Bagaimana mekanisme pendistribusian obat ke UPK? e) Berdasarkan LPLPO, adakah UPK yang obatnya sudah habis atau hampir habis? 9. Ringkasan Masalah-Masalah Yang Ditemukan: 10. Saran Pemecahan Masalah: 11. Rencana Tindak Lanjut (Siapa, kapan dan dimana pemecahan masalah tersebut akan dilaksanakan): ., tgl.. Mengetahui: Kepala Unit Yang disupervisi Pelaksana supervisi:
(...)
()
lxvi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Contoh Materi Supervisi Di Daerah Propinsi
DAFTAR TILIK SUPERVISI PROGRAM PENANGGULANGAN TBC KE PROPINSI
Tanggal kunjungan Nama Propinsi yang di kunjungi Nama petugas yang di supervisi Jabatan : : : : ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
1. Sumber Daya Manusia: a) Tulis nama-nama petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC. b) Kapan terakhir petugas-petugas tersebut mendapat pelatihan. c) Rencanakan pelatihan bagi yang belum dilatih atau yang perlu penyegaran. 2. Laporan Triwulan: a) Apakah laporan triwulan (TBC.07, TBC.08 dan TBC.11) dari kabupaten/kota sudah lengkap diterima di propinsi? b) Apakah propinsi membuat umpan-balik ke kabupaten/kota tentang kelengkapan penerimaan laporan triwulan? (lihat arsip). c) Apakah laporan-laporan tersebut sudah direkap per kabupaten/kota dan dikirim ke pusat? (lihat arsip). d) Apakah data di propinsi sesuai dengan data yang ada di pusat? (validasi data) 3. Review bersama petugas propinsi bagaimana hasil pelaksanaan kegiatan penemuan penderita dan kegiatan pengobatan penderita (per kabupaten/kota): a) Berapa proporsi penderita baru TBC BTA Positif diantara seluruh suspek yang diperiksa? (dihitung dari rekap laporan TBC.07). b) Berapa proporsi penderita BTA Positif diantara semua penderita yang ditemukan? (dihitung dari rekap laporan TBC.07) c) Berapa angka kesembuhan (cure-rate) dihitung dari rekap laporan TBC.08? d) Berapa angka konversi, dihitung dari rekap laporan TBC.11? e) Berapa proporsi penemuan penderita baru BTA positif terhadap perkiraan penderita baru BTA positif yang ada (Case Detection Rate/ CDR)? f) Berapa cakupan penemuan penderita baru semua tipe (BTA pos., BTA neg. dll) per 100.000 penduduk (Case Notification Rate/ CNR)? g) Berapa jumlah sediaan yang di cross check? h) Berapa % PRM yang di cross check, dan berapa PRM yang hasil cross check nya bagus? (error-rate sama atau lebih kecil dari 5%). i) Kabupaten/Kota mana yang pencapaiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan apa kemungkinan penyebabnya?
lxvii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
4. Diskusikan dengan petugas propinsi tentang perencanaan tahunan termasuk pengembangan cakupan unit pelayanan didasarkan pada review hasil kegiatan seperti diatas (butir 3). 5. Supervisi petugas propinsi ke kabupaten / kota: a) Apakah propinsi mempunyai rencana supervisi? b) Bagaimana frekwensi supervisi tersebut? c) Berapa kali supervisi tersebut berhasil dilaksanakan diantara yang direncanakan? d) Siapa yang melaksanakan supervisi? (lihat arsipnya). e) Apakah menggunakan supervisi checklist? (lihat arsipnya) f) Apakah laporan hasil supervisi dikirim (umpan-balik) ke unit yang disupervisi? (lihat arsip surat pengantar). g) Apakah masalah yang ditemukan sudah di tindak-lanjuti? 6. Persediaan Obat dan Bahan-Bahan Pelengkap Bagaimana proses perencanaan untuk pengadaan obat/bahan-bahan tersebut? 7. Kunjungan ke BLK (Balai Laboratorium Kesehatan): a) Apakah penerimaan sediaan dahak untuk di cross check datangnya secara teratur? b) Apakah semua permintaan cross check sudah diperiksa dan hasilnya sudah disampaikan kepada yang memintanya? c) Apakah biaya pemeriksaan cross check sudah dibayarkan? d) Apakah BLK menerima tembusan umpan-balik hitungan error-rate per PRM/Laboratorium yang dibuat Dinas Kesehatan Kab/Kota yang bersangkutan? e) Apakah petugas PRM/Lab.lainnya yang error rate >5% sudah mengikuti magang di BLK. Berapa banyak petugas yang magang dalam 1 tahun terakhir? f) Apakah petugas BLK melakukan supervisi ke PRM/Lab.lainnya yang error rate >5%? g) Apakah reagen ZN dibuat secara bertahap yaitu setiap 3 bulan sekali atau sesuai kebutuhan; apakah pada etiketnya ditulis tanggal pembuatannya, bagaimana cara distribusi reagen tersebut? 8. Ringkasan Masalah-Masalah yang Ditemukan: Saran Pemecahan Masalah: 9. Rencana Tindak Lanjut (Siapa, kapan dan dimana pemecahan masalah tersebut akan dilaksanakan):
lxviii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
., tgl.. Mengetahui: Kepala Unit Yang disupervisi Pelaksana supervisi:
(...)
()
lxix
Program Penanggulangan Tuberkulosis
BAB XI MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program.
Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala dan terus menerus, untuk dapat segera mendeteksi bila ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, supaya dapat dilakukan tindakan perbaikan segera. Evaluasi dilakukan setelah suatu jarak-waktu (interval) lebih lama, biasanya setiap 6 bulan s/d 1 tahun. Dengan evaluasi dapat dinilai sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya dicapai. Dalam mengukur keberhasilan tersebut diperlukan indikator. Hasil evaluasi sangat berguna untuk kepentingan perencanaan program. Masing-masing tingkat pelaksana program (UPK, Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat) bertanggung jawab melaksanakan pemantauan kegiatan pada wilayahnya masing-masing. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, diperlukan suatu sistem pencatatan dan pelaporan baku yang dilaksanakan dengan baik dan benar. Pada prinsipnya semua kegiatan harus dimonitor dan dievaluasi, antara lain kegiatan penatalaksanaan penderita (penemuan diagnosis, dan pengobatan), pelayanan laboratorium, penyediaan obat dan bahan pelengkap lainnya, pelatihan petugas, penyuluhan, advokasi, dan supervisi. Seluruh kegiatan tersebut harus dimonitor baik dari aspek masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Cara pemantauan dilakukan dengan menelaah laporan, pengamatan langsung dan wawancara dengan petugas pelaksana maupun dengan masyarakat sasaran. Indikator Indikator merupakan alat yang paling efektif untuk melakukan monitoring & evaluasi. Indikator adalah variabel yang menunjukkan/menggambarkan keadaan dan dapat digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan. Indikator yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti: Sahih (valid) Sensitif dan Spesifik (sensitive and specific) Dapat dipercaya (realiable) Dapat diukur (measureable) Dapat dicapai (achievable) Indikator bisa dikembangkan diberbagai tingkat administrasi, sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan indikator tersebut. Di tingkat nasional, indikator dikembangkan sebagai alat ukur kemajuan (marker of progress) untuk melihat sejauh mana tujuan telah dicapai.
lxx
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Dalam program penanggulangan TBC, bila 70% dari perkiraan penderita baru yang ada, dapat ditemukan dan diobati, dengan angka kesembuhan 85% dan didukung angka kesalahan laboratorium < 5%, maka dalam waktu 5 tahun, jumlah penderita akan berkurang setengahnya (50%). Indikator nasional berikut dipakai untuk memantau pencapaian target program :
Indikator nasional. Angka penemuan penderita = Case Detection Rate Angka kesembuhan = Cure Rate Angka konversi = Conversion Rate Angka kesalahan laboratorium = Error Rate
Di bawah ini akan diuraikan berbagai indikator yang dapat digunakan, arti dari masingmasing indikator dan tujuan penggunaan indikator diberbagai tingkat dan UPK. Tabel-11 Indikator Yang Dapat Digunakan Di Berbagai Tingkatan
No 1 1. 2. INDIKATOR 2 Proporsi Suspek diperiksa Proporsi penderita TBC paru BTA positif diantara suspek yang diperiksa dahaknya. Proporsi penderita TBC paru BTA positif diantara seluruh penderita TBC Paru TB-06 TB-06 SUMBER DATA 3 PERIODE 4 Bulanan Bulanan PEMANFAAT INDIKATOR UPK 5 Kab/Kota 6 Propinsi 7 Pusat 8 -
3.
TB-01 TB-03 TB-07 TB-01 TB-03 TB-11 TB-01 TB-03 TB-08 TB-12 TB-07 Data kependudukan
Triwulan
4.
Angka Konversi
Triwulan
5. 6. 7.
Angka Kesembuhan Error Rate Case Notification Rate
Triwulan Triwulan Tahunan
lxxi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
TB-07 Data perkiraan jumlah penderita baru BTA positif.
8.
Case Detection Rate
Tahunan
Cara menghitung dan analisa indikator. 1. PROPORSI SUSPEK YANG DIPERIKSA DAHAKNYA Proporsi suspek yang diperiksa adalah : Persentase suspek diantara perkiraan jumlah suspek yang seharusnya ada. Angka ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan. Rumus :
Jumlah suspek yang diperiksa bisa didapatkan dari buku daftar suspek (TBC.06) Perkiraan jumlah penderita BTA positif di Indonesia adalah 13/1000 penduduk. (Global TBC Control - WHO Report, 2000). UPK yang tidak mempunyai wilayah kerja, misalnya rumah sakit, BP4 atau dokter praktek swasta, indikator ini sulit dianalisa, indikator ini tidak dapat dihitung. 2. PROPORSI PENDERITA BTA POSITIF DIANTARA SUSPEK Proporsi penderita BTA positif diantara suspek adalah : Persentase penderita yang ditemukan BTA positif diantara seluruh suspek yang diperiksa sputumnya. Angka ini menggambarkan proses penemuan sampai diagnosis penderita, serta kepekaan menetapkan kriteria suspek. Rumus :
X 100 %
l
lxxii
X 100 %
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Biasanya ditemukan angka sekitar 10%. Bila angka ini terlalu kecil, misalnya 3%, mungkin disebabkan karena penjaringan suspek terlalu longgar. Banyak orang yang tidak memenuhi kriteria suspek, atau ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium. Bila angka ini terlalu besar, misalnya 30%, mungkin disebabkan penjaringan / kriteria suspek terlalu ketat atau ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium (false positive terlalu tinggi). Keadaan ini bisa menyebabkan banyaknya penderita yang tidak terdeteksi atau lolos. 3. PROPORSI PENDERITA TBC PARU PENDERITA TBC PARU TERCATAT. BTA POSITIF DIANTARA SEMUA
Proporsi penderita TBC paru BTA positif diantara semua penderita TBC paru adalah : Persentase penderita TBC paru BTA positif diantara semua penderita TBC paru tercatat. Indikator ini menggambarkan kegiatan penemuan penderita TBC yang menular diantara seluruh penderita TBC paru yang diobati. Rumus: /// Jumlah Penderita TBC BTA Positif (Baru + Kambuh) xxxxxx
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100%
Jlh penderita TBC BTA Pos. (Baru + Kambuh) + Jlh penderita TBC BTA Neg.
Angka ini sebaiknya jangan kurang dari 65%. Bila angka ini jauh lebih rendah, itu berarti kualitas diagnosis rendah, dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan penderita yang menular (penderita BTA Positif). 4. ANGKA KONVERSI (CONVERSION RATE) Angka konversi adalah: Persentase penderita TBC paru BTA positif yang mengalami konversi menjadi BTA negatif setelah menjalani masa pengobatan intensif. Angka konversi dihitung tersendiri untuk tiap klasifikasi dan tipe penderita, BTA postif baru dengan pengobatan kategori-1, atau BTA positif pengobatan ulang dengan kategori2. Indikator ini berguna untuk mengetahui secara cepat kecenderungan keberhasilan pengobatan dan untuk mengetahui apakah pengawasan langsung menelan obat dilakukan dengan benar. Contoh perhitungan untuk penderita baru BTA positif:
Jumlah penderita baru BTA Positif yang diobati
lxxiii
l h
X 100 %
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Di UPK, indikator ini dapat dihitung dari kartu penderita TB.01, yaitu dengan cara mereview seluruh kartu penderita baru BTA Positif yang mulai berobat dalam 3-6 bulan sebelumnya, kemudian dihitung berapa diantaranya yang hasil pemeriksaan dahak negatif, setelah pengobatan intensif (2 bulan). Di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat, angka ini dengan mudah dapat dihitung dari laporan TB.11. Angka minimal yang harus dicapai adalah 80 %. Angka konversi yang tinggi akan diikuti dengan angka kesembuhan yang tinggi pula. Selain dihitung angka konversi penderita baru TBC paru BTA positif, perlu dihitung juga angka konversi untuk penderita TBC paru BTA positif yang mendapat pengobatan dengan kategori 2. 5. ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) Angka kesembuahan adalah : Angka yang menunjukkan persentase penderita TBC BTA positif yang sembuh setelah selesai masa pengobatan, diantara penderita TBC BTA positif yang tercatat. Angka kesembuhan dihitung tersendiri untuk penderita baru BTA positif yang mendapat pengobatan kategori 1 atau penderita BTA positif pengobatan ulang dengan kategori 2. Angka ini dihitung untuk mengetahui keberhasilan program dan masalah potensial.
Contoh perhitungan untuk penderita baru BTA positif dengan pengobatan kategori 1.
Di UPK, indikator ini dapat dihitung dari kartu penderita TB.01, yaitu dengan cara mereview seluruh kartu penderita baru BTA Positif yang mulai berobat dalam 9 - 12 bulan sebelumnya, kemudian dihitung berapa diantaranya yang sembuh, setelah selesai pengobatan. Di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat, angka ini dengan mudah dapat dihitung dari laporan TB.08. Angka minimal yang harus dicapai adalah 85%. Angka kesembuhan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengobatan. Bila angka kesembuhan lebih rendah dari 85%, maka harus ada informasi dari hasil pengobatan lainnya, yaitu berapa penderita yang digolongkan sebagai pengobatan lengkap, default (drop-out atau lalai), gagal, meninggal, dan pindah keluar.
lxxiv
Jumlah penderita baru BTA Positif yang diobati
l h
X 100 %
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Angka default tidak boleh lebih dari 10%, sedangkan angka gagal untuk penderita baru BTA positif tidak boleh lebih dari 4% untuk daerah yang belum ada masalah resistensi obat, dan tidak boleh lebih besar dari 10% untuk daerah yang sudah ada masalah resistensi obat. Selain dihitung angka kesembuhan penderita baru TBC paru BTA positif, perlu dihitung juga angka kesembuhan untuk penderita TBC paru BTA positif yang mendapat pengobatan ulang dengan kategori 2. 6. ERROR RATE Error rate atau angka kesalahan baca adalah : Angka kesalahan laboratorium yang menyatakan persentase kesalahan pembacaan slide/ sediaan yang dilakukan oleh laboratorium pemeriksa pertama setelah di uji silang (cross check) oleh BLK atau laboratorium rujukan lain. Angka ini menggambarkan kualitas pembacaan slide secara mikroskopis langsung laboratorium pemeriksa pertama. Rumus :
X 100 % Jumlah seluruh sediaan yang di cross check
Angka kesalahan baca sediaan (error rate) ini hanya bisa ditoleransi maksimal 5%. Error rate ini menjadi kurang berarti bila jumlah slide yang di cross check (uji silang) relatif sedikit. Pada dasarnya error rate dihitung pada masing-masing laboratorium pemeriksa, di tingkat kabupaten/ kota. Kabupaten / kota harus menganalisa berapa persen laboratorium pemeriksa yang ada diwilayahnya melaksanakan cross check, disamping menganalisa error rate per PRM / PPM / RS / BP4, supaya dapat mengetahui kualitas pemeriksaan slide dahak secara mikroskopis langsung. 7. CASE NOTIFICATION RATE Case Notification Rate (CNR) adalah : Angka yang menunjukkan jumlah penderita baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut.
lxxv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Rumus :
Jumlah penduduk
Angka ini berguna untuk menunjukkan "trend" atau kecenderungan meningkat atau menurunnya penemuan penderita pada wilayah tersebut.
l h
X 100.000
8. CASE DETECTION RATE Case Detection Rate (CDR) adalah : Persentase jumlah penderita baru BTA positif yang ditemukan dibanding jumlah penderita baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Case Detection Rate menggambarkan cakupan penemuan penderita baru BTA positif pada wilayah tersebut. Rumus :
Jumlah penderita baru BTA Positif yang dilaporkan dlm TB.07 Perkiraan jumlah penderita baru BTA Positif
X 100 %
Angka perkiraan nasional penderita baru BTA positif adalah 130/100.000 penduduk (100 200 per 100.000 penduduk). Target Case Detection Rate Program Penanggulangan TBC Nasional : 70% pada tahun 2005, dan tetap dipertahankan pada tahun-tahun selanjutnya.
lxxvi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
BAB XII PERENCANAAN
Perencanaan adalah salah satu kegiatan pokok dalam manajemen. Perencanaan digunakan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada saat ini dan masa yang akan datang dialokasikan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya perencanaan dilakukan oleh semua unit pada setiap tingkat administrasi. Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Propinsi, Laboratorium dan unit lainnya, dengan ruang lingkup yang berbeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit tersebut. Dalam sistem desentralisasi, daerah Kabupaten/Kota akan mendapatkan otonomi seluasluasnya, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam perencanaan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus membuat perencanaan berbasis wilayah atau evidence based planning, yaitu perencanaan yang dibuat secara terpadu dan benar-benar didasarkan pada besarnya masalah, kondisi daerah serta kemampuan sumber daya setempat. Perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terus-menerus tidak terputus sehingga merupakan suatu siklus meliputi: analisis situasi, identifikasi dan menetapkan masalah prioritas, menetapkan tujuan untuk mengatasi masalah, menetapkan alternatif pemecahan masalah, menyusun rencana kegiatan dan penganggaran (POA), menyusun rencana pemantauan dan evaluasi. Tahap pertama perencanaan sebenarnya selesai dengan telah tersusunnya rencana program. Tetapi pelaksanaan program tersebut harus dipantau agar dapat dilakukan koreksi dan dapat dibuat perencanaan ulang (re-planning) untuk waktu selanjutnya. Untuk itu kita mulai lagi membuat analisis situasi atau analisis masalah. Siklus perencanaan yang biasa kita ikuti untuk suatu program adalah satu tahun (perencanaan tahunan) sesuai dengan periode tahun anggaran.
42. ANALISIS SITUASI
Analisis situasi memerlukan data yang lengkap, untuk itu perlu didahului dengan pengumpulan data serta pengolahan data.
lxxvii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
42.1. Pengumpulan data dan pengolahan data
Data yang diperlukan bukan hanya data kesehatan tetapi juga data pendukung dari sektor terkait. Data yang diperlukan dalam program penanggulangan TBC, dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1) Data Umum
Mencakup data geografi dan demografi (penduduk, pendidikan, sosial budaya) serta data non-teknis lainnya. Data ini diperlukan untuk menetapkan target, sasaran dan strategi operasional lainnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.
2) Data Program
Meliputi data tentang penderita TBC, pencapaian program (penemuan penderita, keberhasilan diagnosis, keberhasilan pengobatan), resistensi obat serta data tentang kinerja institusi lainnya. Data ini diperlukan untuk dapat menilai apa yang sedang terjadi, sampai dimana kemajuan program, masalah apa yang dihadapi dan rencana apa yang akan dilakukan.
3) Data Sumber Daya
Meliputi data tentang tenaga (man), dana (money), logistik (material), dan metodelogi yang digunakan (methode). Data ini diperlukan untuk menyusun program secara rasional, sesuai dengan kemampuan serta dapat mengidentifikasikan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi. Semua data tersebut sebaiknya dikumpulkan melalui sistem yang rutin, dengan memanfaatkan sistem pencatatan pelaporan serta sistem surveilens yang baku. Dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan penelitian. Data tersebut diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, serta bentuk lain yang sesuai sehingga mudah untuk membuat analisis. Disamping untuk perencanaan, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti advokasi, diseminasi informasi serta umpan balik.
42.2. Analisis data
Berdasarkan olahan data tersebut dapat dilakukan analisis sesuai keperluan. Analisis diarahkan pada identifikasi masalah yang merupakan tahap berikutnya dan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga dapat diketahui masalah secara benar. Selain data tersebut, perlu juga diperhatikan hal-hal baku yang merupakan ketentuan yang harus diikuti, antara lain kebijaksanaan atau komitmen nasional maupun international.
43. IDENTIFIKASI DAN MENETAPKAN MASALAH PRIORITAS 43.1. Identifikasi masalah
Identifikasi masalah dimulai dengan melihat adanya kesenjangan antara pencapaian dengan target/tujuan yang ditetapkan. Untuk maksud tersebut, gunakan indikator
lxxviii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
utama yaitu angka cakupan (Case Detection Rate), angka kesembuhan, angka konversi dan angka kesalahan pemeriksaan laboratorium (error rate). Dari kesenjangan yang ditemukan, dicari masalah dan penyebabnya. Untuk memudahkan, masalah tersebut dikelompokkan dalam input dan proses, agar tidak ada yang tertinggal dan mempermudah penetapan prioritas masalah dengan berbagai metode yang ada. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah dengan metode tulang ikan (fish bone analysis). Komponen yang dianalisis terdiri dari 5M (man, money, material, method, & market).
43.2. Menetapkan masalah yang prioritas
Diantara semua masalah yang ditemukan, harus dipilih beberapa masalah saja yang merupakan masalah prioritas. Cara memilih masalah prioritas ini juga dapat menggunakan berbagai theori yang telah dikenal. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih prioritas, antara lain:
1) Daya ungkitnya tinggi, artinya bila masalah itu dapat diatasi maka masalah lain akan teratasi juga. 2) Kemungkinan untuk dilaksanakan (feasibility), artinya upaya ini mungkin untuk dilakukan. 44. MENETAPKAN TUJUAN UNTUK MENGATASI MASALAH
Tujuan yang akan dicapai ditetapkan berdasar kurun waktu dan kemampuan tertentu. Beberapa syarat yang diperlukan dalam menetapkan tujuan antara lain:
44.1. Terkait dengan masalah 44.2. Terukur (kuantitatif) 44.3. Rasional (realistis) 44.4. Memiliki target waktu.
Biasanya dibedakan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya cukup satu dan tidak terlalu spesifik. Tujuan umum dapat dipecah menjadi beberapa tujuan khusus yang lebih spesifik dan terukur. Penetapan tujuan ini akan dibahas lebih rinci pada pengembangan program.
45. MENETAPKAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH
Dari masalah prioritas dan tujuan yang ingin dicapai, dapat diidentifikasi alternatif pemecahan masalah. Identifikasi dilakukan dengan mengelompokkan pemecahan masalah. Dalam menetapkan pemecahan masalah, biasanya ditetapkan beberapa alternatif pemecahan masalah yang akan menjadi pertimbangan pimpinan untuk ditetapkan sebagai pemecahan masalah yang paling baik. Seperti pada penetapan tujuan, dalam memilih pemecahan masalah dari
lxxix
Program Penanggulangan Tuberkulosis
berbagai alternatif, pertimbangannya antara lain adalah yang mempunyai daya ungkit terbesar dan dapat dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan. Dapat dilaksanakan dalam arti ada metodologinya dan ada sumber daya yang mendukung
46. MENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN PENGANGGARAN (POA)
Tujuan jangka menengah dan jangka panjang, tidak dapat dicapai sekaligus sebab banyak masalah yang harus dipecahkan sedang sumber daya terbatas, oleh sebab itu perlu ditetapkan pentahapan dalam pengembangan program. Pada saat ini, program penanggulangan TBC, sudah mencapai tahap pengembangan. Pengembangan meliputi pengembangan wilayah dan pengembangan cakupan. Wilayah yang dikembangkan ialah daerah yang belum melaksanakan strategi DOTS. Dalam pengembangan cakupan hendaknya selalu mempertimbangkan peningkatan kualitas.
46.1. Pengembangan wilayah dan unit pelaksana
Pada saat ini hampir seluruh kabupaten / kota telah melaksanakan strategi DOTS, tetapi belum mencakup seluruh puskesmas, rumah sakit, BP4, RSTP dan dokter praktek swasta. Tiap kabupaten / kota diharuskan merencanakan tahapan pengembangan unit pelayanan yang ada didaerahnya masing-masing. Pentahapan didasarkan pada:
1) Besarnya masalah : Perkiraan jumlah penderita TBC BTA Positif. 2) Daya ungkit : Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan tingkat sosial-ekonomi masyarakat. 3) Kesiapan : Tenaga, sarana, dan kemitraan.
Pada tahap awal, pengembangan dilakukan terhadap Puskesmas. Setelah itu baru rumah sakit, BP4, RSTP dan praktek dokter swasta (PDS). Bila ada kabupaten / kota yang belum melaksanakan strategi DOTS, pengembangan DOTS diharapkan dapat dimulai dengan beberapa Puskesmas dulu. Langkah yang diambil sama dengan langkah yang telah ditetapkan didepan. Data tentang pencapaian program tentu saja belum ada, namun perlu didukung dengan data penyakit, data kunjungan puskesmas dan rumah sakit sehingga dapat diperkirakan besarnya masalah.
46.2. Peningkatan Cakupan
Yang dimaksud dengan peningkatan cakupan adalah peningkatan cakupan penemuan dan pengobatan penderita; dengan kata lain peningkatan proporsi dari penderita baru yang ditemukan dan diobati oleh suatu unit pelayanan dibandingkan dengan perkiraan jumlah penderita yang ada diwilayah tersebut (lihat uraian tentang indikator program).
lxxx
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Cakupan penemuan dan pengobatan ini penting, sebab dampak epidemiologis, yaitu penurunan jumlah penderita, sangat tergantung pada tingkat cakupan penemuan dan pengobatan tersebut. WHO, saat ini menetapkan bahwa target cakupan penemuan tersebut adalah 70%, dengan cure rate minimal 85%, conversion rate minimal 80% dan error rate < 5% harus dicapai lebih dulu. Dengan kata lain, peningkatan cakupan penemuan dan pengobatan disuatu wilayah atau unit pelaksana hanya dilakukan bila kualitas program sudah memenuhi standar (cure rate > 85%, angka konversi > 80% dan error rate < 5%). Peningkatan cakupan dapat dilakukan dengan:
1) Peningkatan KIE, seperti penyuluhan (promosi) dan pendekatan penemuan berbasis masyarakat (community based approach = CBA). CBA dapat dilaksanakan di desa yang diperkirakan banyak penderita TBC dengan syarat kualitas program sudah memenuhi standar, tetapi penemuan penderita masih sangat rendah. Proses dari CBA dimulai dengan penyuluhan kepada masyarakat desa secara intensif; seminggu kemudian petugas Puskesmas datang ke desa tersebut untuk memeriksa suspek TBC di desa tersebut yang datang secara sukarela. 2) Perluasan unit pelaksana. 3) Pemeriksaan kontak serumah dengan penderita BTA positif.
Salah satu prinsip yang harus dianut adalah penemuan penderita bukan dengan cara active case finding, tetapi harus secara passive case finding dengan active promotion dimana penjaringan suspek dilakukan hanya di unit pelayanan kesehatan dengan penyuluhan aktif ke masyarakat.
46.3. Peningkatan Kualitas
Sebelum peningkatan cakupan, baik melalui peningkatan KIE atau dengan perluasan unit pelaksana (pengembangan wilayah), yang mutlak harus dilakukan adalah peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ini mencakup segala aspek mulai dari penemuan, diagnosis penderita, pengobatan dan case holding penderita, sampai pada pencatatan pelaporan. Masing-masing aspek tersebut, perlu dinilai semua unsurnya, apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara garis besar dapat dinilai dengan beberapa indikator utama yaitu angka konversi (conversion rate), angka kesembuhan (cure rate) dan angka kesalahan baca sediaan (error rate). Analisis kualitas ini diperlukan untuk merencanakan berbagai kegiatan perbaikan yang menyangkut masukan (input) dan proses.
lxxxi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
46.4. Pemetaan Wilayah
Sebelum melakukan pengembangan wilayah atau peningkatan cakupan perlu dilakukan penilaian terhadap unit pelaksana secara menyeluruh mengenai kualitas dan cakupan. Dari hasil penilaian atau pemantauan ini, unit pelaksana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu : Kelompok I: Kualitas belum memenuhi standard (cure rate < 85%, error rate >5%). Cakupan penemuan rendah (penemuan penderita < 70%). Yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas. Belum perlu meningkatkan cakupan Kualitas sudah memenuhi standard (cure rate 85%, error rate 5%). Cakupan penemuan rendah (penemuan penderita < 70%). Sudah boleh meningkatkan cakupan dengan tetap mempertahankan kualitas Kualitas sudah memenuhi standard (cure rate 85%, error rate 5%). Cakupan penemuan tinggi (penemuan penderita 70%). Dapat lebih meningkatkan cakupan dengan tetap mempertahankan kualitas
Kelompok II:
Kelompok III:
46.5. Penetapan Sasaran dan Target 1. Sasaran Wilayah
Sasaran wilayah ditetapkan dengan memperhatikan besarnya masalah, daya ungkit dan kesiapan daerah (lihat butir 5.1)
2. Sasaran Penduduk
Sasaran pada dasarnya adalah seluruh penduduk. Saat ini penderita TBC anak sudah dirasakan menjadi masalah, sehingga anak dibawah 15 tahun juga harus diperhitungkan sebagai sasaran.
3. Penetapan Target
Target ditetapkan dengan memperkirakan jumlah penderita TBC baru yang ada disuatu wilayah. Perkiraan tersebut dapat dihitung dengan survai prevalensi, tetapi survai tersebut sulit dan mahal. Untuk mengatasi hal tersebut, secara nasional ditetapkan pedoman berdasarkan angka perkiraan WHO yaitu angka insiden kasus baru BTA positif adalah sebesar 130 per 100.000 penduduk, dengan kata lain, 130 kasus baru BTA positif dalam 100.000 penduduk. Target cakupan (Case Detection Rate) ditetapkan sesuai kemampuan, dan ditingkatkan secara bertahap. Secara nasional target cakupan penemuan penderita ditetapkan sebesar 70% dari jumlah penderita yang diperkirakan pada tahun 2005.
lxxxii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
46.6. Penyusunan Anggaran
Dalam menyusun kebutuhan anggaran secara lengkap, prinsip-prinsip penyusunan program dan anggaran terpadu hendaknya dapat diikuti, antara lain adalah:
1) Mengikuti langkah-langkah perencanaan seperti tersebut diatas. 2) Mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh. 3) Mempertimbangkan semua potensi sumber dana yang bisa dimobilisasikan.
lxxxiii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Secara skematis dapat dilihat pada bagan di bawah ini:
APBD - DABPD/DIKDA (Desentr) - DIP/DIK (Dekons)
TopDown (Kebijakan)
Analisis Biaya
APBN - DIK - DIP
Analisis Situasi Kes
Masalah Kese hatan
Seleksi Alter natif
Penyusu nan Program
Penganggaran
Bottom Up
Lintas Sektor dan Kemitraan
BLN
Askes
PERENCANAAN TERPADU
PENGANGGARAN TERPADU
Perlu diperhatikan bahwa penyusunan anggaran didasarkan pada kebutuhan program seperti tersebut diatas, sedangkan pemenuhan dana harus diusahakan dari berbagai sumber. Dengan kata lain disebut program oriented, bukan budget oriented.
46.7. Perencanaan Kegiatan
Setelah selesai dengan langkah penyusunan anggaran, tiap kabupaten / kota diwajibkan menyusun rencana kegiatan secara lengkap. Formatnya mengacu pada contoh dibawah ini:
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Pendahuluan Analisis situasi dan besarnya masalah Masalah prioritas Tujuan Sasaran dan target Pelaksanaan:
Kegiatan Lokasi pelaksanaan Kebutuhan tenaga dan pelatihan Kebutuhan OAT dan logistik lain Kebutuhan dana dan sumber pendanaan
lxxxiv
7) Supervisi dan Pemantauan
Program Penanggulangan Tuberkulosis
8) Evaluasi MENYUSUN RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Dalam menyusun perencanaan selain menyusun hal-hal yang telah diuraikan diatas perlu disusun rencana pemantauan dan evaluasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pemantauan dan evaluasi meliputi: 46.8. Jenis-jenis kegiatan dan indikator, 46.9. Cara pemantauan, 46.10. Pelaksana (siapa yang memantau), 46.11. waktu dan frekuensi pemantauan (bulanan/triwulan/tahunan), 46.12. Rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
lxxxv
Program Penanggulangan Tuberkulosis
BAB XIII PENGELOLAAN LOGISTIK
Pengelolaan logistik program penanggulangan TBC merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan. Logistik program penanggulangan TBC terdiri dari 2 bagian besar yaitu logistik OAT dan logistik lainnya.
47. PENGELOLAAN OAT
Secara umum proses pengelolaan OAT untuk program digambarkan sebagai berikut:
LPLPO PENGGUNAAN DI UPK
PERE
KETERSEDIAAN OAT PENGADAAN PENYIMPANAN & PENDISTRIBUSIAN
47.1.
Perencanaan Kebutuhan Obat
Rencana kebutuhan Obat untuk UPK dilaksanakan dengan pendekatan bottom up planning di tingkat kabupaten/kota berdasarkan data Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari semua UPK di kabupaten/kota. Agar pengadaan obat lebih terkendali maka daftar obat untuk pelayanan kesehatan di kabupaten/kota dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, sebagai berikut:
Obat Sangat Sangat Esensial (SSE) yaitu obat yang berisiko tinggi apabila tidak tersedia atau terlambat disediakan, sulit didapat di
lxxxvi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
daerah dan obat program yang harus dijamin ketersediaannya secara tepat waktu, tepat jenis dengan mutu terjamin untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di kabupaten / kota, misalnya OAT. Obat Sangat Esensial (SE) yaitu obat yang diperlukan dan sering digunakan serta masih mengandung risiko dalam hal kemampuan suplainya di daerah. Obat Esensial (E) yaitu obat yang diperlukan dan sering digunakan serta mudah di suplai di daerah kabupaten. 1.1.1. Tingkat Unit Pelayanan Kesehatan
Unit pelayanan kesehatan menghimpun data, merencanakan kebutuhan tahunan berdasarkan pedoman yang ditetapkan, yaitu: pencapaian penemuan penderita BTA positif pada tahun sebelumnya (perinci berdasarkan kategori OAT dan sisipan), pengembangan cakupan, buffer-stock, dikurangi sisa persediaan OAT yang ada. Perhitungan tersebut (cakupan penemuan tahun sebelumnya ditambah pengembangan cakupan dikurangi sisa persediaan) dipakai sebagai dasar perencanaan kebutuhan obat yang dibawa dalam rapat yang dilaksanakan oleh Tim Perencanaan Obat Terpadu.
1.1.2. Tingkat Kabupaten/Kota
Perencanaan kebutuhan OAT di kabupaten/kota dilakukan terpadu dengan perencanaan obat lainnya dengan cara merekapitulasi usulan kebutuhan masing-masing UPK, rencana pengembangan, buffer stock dan sisa OAT yang ada di GFK (Gudang Farmasi Kabupaten). Tim Perencanaan Obat Terpadu daerah kabupaten/kota dibentuk dengan keputusan Bupati / Kepala Daerah kabupaten/kota yang didalamnya termasuk unsur Dinas Kesehatan dan GFK.
1.1.3. Tingkat Propinsi
Perencanaan OAT di propinsi mengikuti prosedur tetap perencanaan obat yang ada di propinsi. Perencanaan ini diteruskan ke pusat karena OAT termasuk paket obat Sangat Sangat Essensial (SSE).
1.2. Pengadaan OAT
Pengadaan OAT dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
lxxxvii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
1.3. Penyimpanan dan pendistribusian OAT
OAT yang telah diadakan, dikirim langsung ke GFK, diterima dan diperiksa oleh Panitia Penerima Obat yang telah dibentuk di kabupaten/ kota. Penyimpanan obat harus disusun berdasarkan FEFO (First Expired First Out), artinya, obat yang kadaluarsanya lebih awal harus diletakkan didepan agar dapat didistribusikan lebih dulu. Pengiriman OAT disertai dengan dokumen yang memuat jenis, jumlah, kemasan, nomor batch dan bulan serta tahun kadaluarsa. OAT disimpan di GFK sesuai persyaratan penyimpanan obat. Distribusi OAT dari GFK ke UPK dilakukan sesuai permintaan yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan.
1.4. Pengawasan Mutu, Pemantauan dan Dinamika Logistik OAT
Pengawasan dan pengujian mutu OAT dimulai dengan pemeriksaan sertifikat analisis pada saat pengadaan. Setelah OAT sampai di daerah, pengawasan dan pengujian mutu OAT dilakukan oleh Balai POM. Pemantauan OAT dilakukan dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintan Obat (LPLPO) yang berfungsi ganda, untuk menggambarkan dinamika logistik dan merupakan alat pencatatan / pelaporan. Dinas Kesehatan bersama GFK membuat laporan OAT menggunakan formulir TBC-13. Pembinaan teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina Obat Propinsi. Secara fungsional pelaksana program TBC propinsi dan daerah kabupaten / kota juga melakukan pembinaan pada saat supervisi.
2. PENGELOLAAN LOGISTIK LAINNYA 2.1. Mikroskop
Dalam pengelolaan mikroskop perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
2.1.1. Semua unit pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan mikroskopis dahak (PRM, PPM, rumah sakit, BP4, dan RSTP pelaksana DOTS) harus mempunyai mikroskop binokuler; minimal 1 mikroskop untuk setiap unit. 2.1.2. Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan mikroskop dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau bantuan swasta. 2.1.3. Standar ditetapkan oleh Program TBC Nasional 2.1.4. Mikroskop dilengkapi dengan spare parts, tempat penyimpanan yang memenuhi syarat (storage box) 2.2. Bahan-bahan Habis Pakai 2.2.1. Sputum pot = jumlah perkiraan kasus BTA positif yang akan diobati x 36 buah.
lxxxviii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
2.2.2. Kaca sediaan = jumlah perkiraan kasus BTA positif yang akan diobati x 36 keping. 2.2.3. Larutan Ziehl Neelsen = jumlah kaca sediaan x 3 cc untuk tiap jenis larutan pewarna. 2.2.4. Asam Alkohol pro analisis = jumlah kaca sediaan x 5 cc. 2.2.5. Kertas pembersih lensa mikroskop untuk setiap laboratorium yang melakukan pewarnaan dan pemeriksaan sediaan. 2.2.6. Formulir pencatatan dan pelaporan, jumlah disesuaikan kebutuhan. 2.3. Bahan tidak habis pakai
Slide Box, Rak pewarna & pengering, Lampu speritus, Ose, Botol plastik bercorong pipet dll.
lxxxix
Program Penanggulangan Tuberkulosis
BAB XIV
PELATIHAN Pelatihan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas tenaga dalam hal pengetahuan, sikap dan ketrampilan untuk pengelolaan program TBC menjadi penting, mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Pelatihan diberikan kepada semua tenaga yang terkait dengan Program Penanggulangan TBC, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan di semua jenjang administrasi pelaksana program. Cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dapat dilakukan melalui pelatihan, orientasi, lokakarya, magang, seminar dan diskusi ilmiah.
1. SASARAN LATIH.
1.1. Tenaga Kesehatan Dibedakan berdasarkan jabatan dan profesi, antara lain dokter umum, dokter spesialis, paramedis keperawatan, tenaga laboratorium serta menurut tugas dan fungsinya (Kepala Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Seksi, Wasor dan lain-lain). 1.2. Tenaga Non-Kesehatan Yang perlu mendapatkan pelatihan atau orientasi antara lain pimpinan daerah, pamong desa, pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader, PMO. 1.3. Organisasi Profesi Kesehatan. Peran organisasi profesi kesehatan sangat besar dalam mendukung keberhasilan program Penanggulangan TBC. Untuk organisasi profesi lebih ditekankan pada orientasi, seminar, loka karya pentaloka, diseminasi informasi, advokasi dan diskusi ilmiah. Organisasi profesi dimaksud antara lain IDI, PDPI, PAPDI, IDAI, POGI, IBI, PPNI, HAKLI, IAKMI. 1.4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bagi LSM terkait, antara lain PPTI, bisa dilakukan orientasi dan diseminasi informasi agar mampu mengoptimalkan kemampuan dan potensi yang ada dalam mendukung penanggulangan TBC nasional. 1.5. Institusi Pendidikan Kesehatan Tenaga pengajar perlu diberikan orientasi program TBC nasional. Peserta didik perlu diberikan pengetahuan tentang program penanggulangan TBC nasional melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
xc
Program Penanggulangan Tuberkulosis
1.6. Masyarakat Masyarakat juga perlu diberi informasi melalui penyuluhan, dengan tujuan untuk menyebar luaskan informasi program penanggulangan TBC nasional kepada anggota keluarganya. 2. MATERI PELATIHAN. Materi pelatihan disesuaikan dengan sasaran peserta latih dan tujuan pelatihan, yang disampaikan dalam bentuk modul dan bahan lainnya.
3. KEGIATAN PELATIHAN.
Pelaksanaan pelatihan yang baik, harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 3.1. Menyusun Rencana Pelatihan. Rencana Pelatihan mencantumkan kegiatan-kegiatan antara lain: a. Training Need Assesment (TNA). TNA perlu dilakukan karena calon peserta latih mempunyai pengalaman dan dasar pendididkan yang berbeda. TNA dilaksanakan untuk menentukan jenis pelatihan yang diperlukan sesuai kelompok sasaran. b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelatihan. Menyusun Kerangka Acuan. Menyusun jadwal dan pengorganisasian pelatihan. Menyusun Kebutuhan Tenaga Pengajar dan Fasilitator Menyusun Kebutuhan Tempat dan sarana Latihan. c. Menyusun rencana evaluasi pasca pelatihan. 3.2. Pelaksanaan a. Pelatihan seharusnya dilaksanakan sebelum pelaksanaan program. b. Pelatihan harus dilaksanakan dengan cara belajar aktif (active learning) berdasarkan situasi tugas dilapangan (task-oriented) dengan penugasan yang mengacu pada pemecahan masalah (problem solving). Metode pelatihan dapat berupa tatap muka, penugasan, dan praktek lapangan. c. Proses pelatihan perlu di monitor dan di evaluasi, untuk itu perlu dibuat instrumennya. Pre test dan post test Evaluasi setiap materi. Evaluasi harian pelaksanaan pelatihan. Evaluasi pelatih / fasilitator Evaluasi praktek kerja dilapangan. d. Penyusunan laporan pelatihan untuk kepentingan tindak lanjut. e. Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan.
xci
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Lampiran 1
Formulir Pencatatan dan Pelaporan 1.1. Formulir Kartu Pengobatan TBC (TB-01). 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. Formulir Kartu Identitas Penderita (TB-02). Formulir Register TBC Kabupaten (TB-03). Formulir Register Laboratorium TB (TB-04). Formulir Permohonan Laboratorium TBC Untuk Pemeriksaan Dahak (TB-05). Formulir Daftar Tersangka Penderita (Suspek) yang Diperiksa Dahak SPS (TB-06). Formulir Laporan Triwulan Penemuan Kasus Baru dan Kambuh (TB-07). Formulir Rekapitulasi TB-07 Blok 1 Per Kabupaten/Kota. Formulir Rekapitulasi TB-07 Blok 2 Per Kabupaten/Kota. Formulir Laporan Triwulan Hasil Pengobatan Penderita TBC Paru yang Terdaftar 1215 Bulan Lalu (TB-08). Formulir Rekapitulasi TB-08 Penderita Kambuh Per Kabupaten/Kota. Formulir Rekapitulasi TB-08 Penderita Baru BTA Negatif Rontgen Positif Per Kabupaten/Kota. Formulir Rekapitulasi TB-08 Penderita Baru BTA Positif Per Kabupaten/Kota. Formulir Rujukan/Pindah Penderita TBC (TB-09). Formulir Hasil Akhir Pengobatan dari Penderita TBC Pindahan (TB-10). Formulir Laporan Triwulan Hasil Pemeriksaan Dahak Akhir Tahap Intensif untuk Penderita Terdaftar 3-6 Bulan Lalu (TB-11). Formulir Pengiriman Sediaan untuk Cross Check (TB-12). Formulir Rekapitulasi TB-12 Propinsi. Formulir Rekapitulasi TB-12 Kabupaten/Kota. Formulir Laporan Penerimaan dan Pemakaian OAT di Daerah Kabupaten/Kota (TB13). Formulir Rekapitulasi TB-13 Propinsi.
xcii
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Lampiran 2
2.1. Uraian Tugas Program TB untuk Petugas Kabupaten/Kota 2.2. Uraian Tugas Program TB untuk Petugas Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) 2.3. Contoh Analisis Data Hasil Kegiatan di UPK 2.4. Daftar Kepustakaan
xciii
Anda mungkin juga menyukai
- Mikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaDari EverandMikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (11)
- Program Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaDari EverandProgram Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9)
- Panduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanDari EverandPanduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)
- Pembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisDari EverandPembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (13)
- Manfaat Gerakan Wudhu Untuk Kesehatan Tubuh ManusiaDari EverandManfaat Gerakan Wudhu Untuk Kesehatan Tubuh ManusiaPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (3)
- Coronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Dari EverandCoronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Merawat penyakit kencing manis tanpa ubatDari EverandMerawat penyakit kencing manis tanpa ubatPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (3)
- Buku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!Dari EverandBuku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (4)
- Mikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaDari EverandMikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaPenilaian: 2.5 dari 5 bintang2.5/5 (2)
- Paparan Kapus PKM Jalan Gedang Tanggal 16Dokumen37 halamanPaparan Kapus PKM Jalan Gedang Tanggal 16PUSKESMAS100% (2)
- Tumbuhan Herbal Yang Berkhasiat Mencegah Wabah Penyakit Edisi Bahasa Inggris 2021Dari EverandTumbuhan Herbal Yang Berkhasiat Mencegah Wabah Penyakit Edisi Bahasa Inggris 2021Belum ada peringkat
- Teknik Asas Pembiakan Hibrid Ikan Keli Thailand (Clarias sp.)Dari EverandTeknik Asas Pembiakan Hibrid Ikan Keli Thailand (Clarias sp.)Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Pedoman Nasional Penanggulangan TuberkulosisDokumen168 halamanPedoman Nasional Penanggulangan TuberkulosisinkaranisBelum ada peringkat
- Pedoman P2PDokumen19 halamanPedoman P2PDiah Sakuntala100% (4)
- PNPK TBDokumen155 halamanPNPK TBshanty100% (4)
- Kak TB ParuDokumen6 halamanKak TB ParuNIKENBelum ada peringkat
- Buku Pedoman Nasional Penanggulangan TBCDokumen131 halamanBuku Pedoman Nasional Penanggulangan TBCHasrapriliana Hersya100% (1)
- KAP Prog TBDokumen7 halamanKAP Prog TBSanusiBelum ada peringkat
- Sop TBDokumen8 halamanSop TBNunis Nur AzizahBelum ada peringkat
- Pedoman Ispa 2020Dokumen15 halamanPedoman Ispa 2020Puskesmas PamarayanBelum ada peringkat
- Program Kerja Progran TBDokumen9 halamanProgram Kerja Progran TBRizki OktaBelum ada peringkat
- Pedoman TBCDokumen21 halamanPedoman TBCanwar1hidayatBelum ada peringkat
- Pedoman P2Dokumen11 halamanPedoman P2RinaBelum ada peringkat
- Pedoman Internal Program ISPADokumen13 halamanPedoman Internal Program ISPAsapingi100% (1)
- Pdca IspaDokumen13 halamanPdca IspakreatifilmuBelum ada peringkat
- Buku Pedoma TBDokumen131 halamanBuku Pedoma TBAnty FftBelum ada peringkat
- Sop PKM BaupangaDokumen54 halamanSop PKM BaupangarosBelum ada peringkat
- Penemuan Pasien TBDokumen51 halamanPenemuan Pasien TBkelas khusus100% (1)
- Kak Pelaksanaan Program SurveilansDokumen5 halamanKak Pelaksanaan Program SurveilansRonny Jamaluddin50% (6)
- Pedoman Internal Program ISPADokumen13 halamanPedoman Internal Program ISPAAisyah FitriaBelum ada peringkat
- Uraian Tugas Upaya Kesehatan MasyarakatDokumen13 halamanUraian Tugas Upaya Kesehatan MasyarakatdesiBelum ada peringkat
- Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana TuberkulosisDokumen120 halamanPedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana TuberkulosisMokhamad Suyono YahyaBelum ada peringkat
- Tupoksi PKM DumaginDokumen8 halamanTupoksi PKM DumaginInffo Dumagin NoBelum ada peringkat
- MI.3 MANAJEMEN TB DI FKTP 2 240118 - PW MI.3 Pelat FasyankesDokumen20 halamanMI.3 MANAJEMEN TB DI FKTP 2 240118 - PW MI.3 Pelat FasyankesWAHYUBelum ada peringkat
- Ppi.1.Ep.4 Rka PpiDokumen7 halamanPpi.1.Ep.4 Rka PpiFikri JafarBelum ada peringkat
- A. Modul Kebijakan Penanggulangan TB (MD1) 2017Dokumen63 halamanA. Modul Kebijakan Penanggulangan TB (MD1) 2017humas RSUHBBelum ada peringkat
- New Mi.3 - Manajemen TB Di FKRTLDokumen18 halamanNew Mi.3 - Manajemen TB Di FKRTLfitri lestariBelum ada peringkat
- Rka PpiDokumen8 halamanRka PpiDWI DYAHBelum ada peringkat
- Pedoman Pelayanan Tuberkulosis Di RSBTDokumen109 halamanPedoman Pelayanan Tuberkulosis Di RSBTnudiaBelum ada peringkat
- PEDOMAN TB BLM FiksDokumen21 halamanPEDOMAN TB BLM FiksRetnoBelum ada peringkat
- Buku Pedoman Nasional Penatalaksanaan TuberkulosisDokumen131 halamanBuku Pedoman Nasional Penatalaksanaan TuberkulosistanniairawanBelum ada peringkat
- KAK Surveilans 2019Dokumen4 halamanKAK Surveilans 2019pujiBelum ada peringkat
- KAK SURVEILANS TPDokumen4 halamanKAK SURVEILANS TPAndiChumaidiFajriBelum ada peringkat
- 4415 2.panduan TBDokumen2 halaman4415 2.panduan TBIrfan Husni MubarokBelum ada peringkat
- Bab 2Dokumen18 halamanBab 2wahyuni.waBelum ada peringkat
- Program Kerja TB Dots 2022Dokumen18 halamanProgram Kerja TB Dots 2022ayu novyaningtiasBelum ada peringkat
- COntoh RKA PPIDokumen8 halamanCOntoh RKA PPIDedi SaputraBelum ada peringkat
- PNPK TBDokumen120 halamanPNPK TBAditya Perdana Dharma Wiguna100% (3)
- Kak TBDokumen5 halamanKak TBSuciiRahayyuBelum ada peringkat
- 2.7 - Prognas - Hiv - TBDokumen27 halaman2.7 - Prognas - Hiv - TBSadikBelum ada peringkat
- 1.pedoman P2PDokumen13 halaman1.pedoman P2PdedymatoriBelum ada peringkat
- MI.2 Modul Pengobatan FKTP FKRTLDokumen81 halamanMI.2 Modul Pengobatan FKTP FKRTLVinna KusumawatiBelum ada peringkat
- Pedoman TB 2021Dokumen24 halamanPedoman TB 2021Sandy Pensi HuntingBelum ada peringkat
- Kerangka Acuan Program P4Dokumen6 halamanKerangka Acuan Program P4Galuh AjengBelum ada peringkat
- Modul 1Dokumen193 halamanModul 1Esrom Tumpal silalahiBelum ada peringkat
- Kerangka Acuan Posyandu Paru SehatDokumen3 halamanKerangka Acuan Posyandu Paru SehatIrawan AjaBelum ada peringkat
- 1 - 7 - Moch. Joko Wediarto - 21 Juni 2021Dokumen8 halaman1 - 7 - Moch. Joko Wediarto - 21 Juni 2021Ikhlas SabarimanBelum ada peringkat
- Studi Tiru PROGNASDokumen3 halamanStudi Tiru PROGNASFadly SyifaBelum ada peringkat
- Kerangka Acuan TB 2Dokumen7 halamanKerangka Acuan TB 2defriBelum ada peringkat