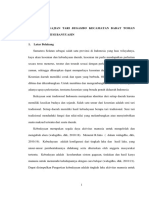319-Article Text-625-1-10-20210109
319-Article Text-625-1-10-20210109
Diunggah oleh
Ekha NatiJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
319-Article Text-625-1-10-20210109
319-Article Text-625-1-10-20210109
Diunggah oleh
Ekha NatiHak Cipta:
Format Tersedia
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
22 Universitas Muhammadiyah Kupang
ANALISIS MAKNA SIMBOLIK “MAKOSU” DALAM RESEPSI PERNIKAHAN PADA
MASYARAKAT DESA RETRAEN KECAMATAN AMARASI SELATAN
KABUPATEN KUPANG
OLEH
Yerlin Rosita Siki1
Oryenes Boymau2
yerlin.siki@yahoo.com
Universitas Aryasatya Deo Muri Kupang Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
ABSTRAK
Rumusan masalah adalah bagaimanakah makna simbolik “Makosu” dalam resepsi
pernikahan pada masyarakat Retraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang? Tujuan
Penelitian: a). Untuk mengetahui makna simbolik “Makosu” dalam acara resepsi pernikahan di
Desa Retraen Kecamatan Amarasi Selatan. Dalam penelitian ini digunakan Teori Semiotik. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan
karena penelitian ini menggunakan data deskriptif dengan cara mendeskripsikan sesuatu yang sudah
ada, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian nonstastik. Data dikumpulkan berupa
kata-kata bukan berupa angka. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa “ Makna Simbolik yang Terkandung dalam “Makosu” dalam Resepsi
Pernikahan pada Masyarakat Desa Retraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupatan Kupang adalah:
1) Makna Kasih Sayang; 2) makna Kekeluargaan; dan 3) Makna Budaya.
Kata Kunci: Makna Simbolik, Makosu, Resepsi Pernikahan
1. Pendahuluan
Amarasi merupakan suatu kesatuan adat yang bermula dari komunitas adat yang memiliki
latar belakang kehidupan yang sama, dengan demikian maka kesatuan itu dinyatakan dalam
identitas Atoni Amarasi yang menempati Timor Tenggara bertepikan Laut Timor di bagian Selatan
Indonesia. Masyarakat Amarasi menggunakan bahasa Dawan (Uab Meto), namun bahasa Dawan
yang digunakan adalah Bahasa Dawan dialek Amarasi, yang selanjutnya disingkat BDA. Perbedaan
bahasa Dawan dan BDA misalnya kata baik dalam Bahasa Dawan yaitu Leko sedangkan untuk
BDA yaitu Reko.
Dalam BDA terdapat dua dialek yaitu Dialek Kotos dan Dialek Ro’is. Dialek Kotos adalah
dialek yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Amarasi sedangkan Dialek Ro’is
digunakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Timur,
dan Kecamatan Amarasi Barat.
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
23 Universitas Muhammadiyah Kupang
Secara realitas, kehidupan masyarakat Amarasi juga masih memelihara dengan teguh
beberapa tradisi yang memiliki makna bagi pola hidup masyarakat Amarasi, tradisi yang masih
eksis terpelihara merupakan suatu warisan kebudayaan yang harus dipertahankan dalam kondisi
kemajuan masa sekarang. Ada pun kebudayaan atau tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat
Amarasi misalnya: ciri khas kain tenun adat yang berbeda dari etnis Atoni Meto lainnya di Timor,
tradisi peminangan wanita, tradisi Se Nonoh, dan tradisi pernikahan adat. Pernikahan pada masa
kini sudah mengalami perubahan dengan sistem inkulturasi di mana semua tatacara adat sebagai
simbol dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan Yang Maha Esa.
Perkawinan atau nikah adat merupakan suatu kegiatan yang memakan waktu yang cukup
terhitung perkenalan, peminangan, janji nikah di gereja, Se Nonoh atau pemindahan marga dan
puncak dari acara pernikahan selalu diisi dengan hiburan atau yang lazim dikenal dengan istilah
acara bebas. Sebelum acara bebas ini dilakukan maka keluarga melakukan acara “Makosu”.
Tradisi “Makosu” menjadi aset kebudayaan bagi masyarakat Kabupaten Kupang khususnya
wilayah Amarasi secara turun-temurun. Tradisi ini dilakukan pada malam resepsi penikahan pada
pembukaan acara hiburan. Tradisi “Makosu” pada masa kini sudah dikolaborasikan dengan
permainan yang dilakukan oleh undangan di mana undangan disuruh memetik pinang yang sudah
diberi tanda pada beberapa buah, kemudian yang mendapatkan pinang itu akan mendampingi
pasangan dalam tarian “Makosu”. Kedua mempelai menari dan dikelilingi oleh para undangan
pendamping, selanjutnya para undangan bebas memberikan uang kepada kedua mempelai dengan
cara uang kertas dijepit dengan lidih atau kayu kemudian ditusuk pada sanggul atau ikat kepala
kedua mempelai.
Tradisi “Makosu” pada masa kini menjadi kebiasaan umum masyarakat etnis Atoni Meto
Kabupaten Kupang, khususnya di Amarasi. Sebagai warisan leluhur, maka tarian “Makosu” ini
bukan saja memiliki makna rekreatif yang menghibur kedua mempelai atau para undangan, namun
secara adat tarian ini memiliki makna yang sangat berpengaruh bagi masyarakat secara umum
terlebih khususnya bagi kedua mempelai dan keluarganya.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah adalah bagaimanakah
makna Simbolik “Makosu” dalam resepsi pernikahan pada masyarakat Retraen Kecamatan Amarasi
Selatan Kabupaten Kupang?. Berdasarkan masalah yang diangkat makah Tujuan dalam Penelitian
ini adalah untuk mengetahui makna Simbolik “Makosu” dalam acara resepsi pernikahan di Desa
Retraen Kecamatan Amarasi Selatan.
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
24 Universitas Muhammadiyah Kupang
2. Teori dan Konsep
2.1 Teori
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Semiotik. Semiotika berasal dari kata
Yunani semeion, yang berarti tanda. Semieon adalah istilah yang digunakan oleh orang Greek untuk
merujuk kepada sains yang mengkaji sistem perlambangan atau sistem tanda dalam kehidupan
manusia (Hartoko, 1986:131). Daripada akar kata inilah terbentuknya istilah semiotik, Istilah yaitu
kajian sastra yang bersifat saintifik yang meneliti sistem perlambangan yang berhubung dengan
tanggapan dalam karya. Menurut Mana Sikana, pendekatan semiotik melihat karya sastra sebagai
satu sistem yang mempunyai hubungan dengan teknik dan mekanisme penciptaan sebuah karya ia
juga memberi tumpuan kepada penelitian dari sudut ekspresi dan komunikasi (Sobur, 2004).
Semiotik adalah sebuah disiplin ilmu sains umum yang mengkaji sistem perlambangan di
setiap bidang kehidupan. Ia bukan saja merangkum sistem bahasa tetapi juga merangkum lukisan,
ukiran, fotografi mahupun pementasan drama atau wayang gambar. Ia wujud sebagai teori
membaca dan menilai karya dan merupakan satu displin yang bukan sempit keupayaannya. Justru
itu ia boleh dimandatkan ke dalam pelbagai bidang ilmu dan boleh dijadikan asas kajian sebuah
kebudayaan. Oleh karena sosiologi dan linguistik merupakan bidang kajian yang mempunyai
hubungan di antara satu sama lain, semiotik yang mengkaji sistem tanda dalam bahasa juga
berupaya mengkaji wacana yang mencerminkan budaya dan pemikiran. Justru, yang menjadi
perhatian semiotik adalah mengkaji dan mencari tanda-tanda dalam wacana serta menerangkan
maksud daripada tanda-tanda tersebut dan mencari hubungannya dengan ciri-ciri tanda itu untuk
mendapatkan makna signifikasinya
Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa pengalaman,
pikiran, perasaan, gagasan dan lain-lain. Jadi, yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan hanya
bahasa saja, melainkan berbagai hal yang melingkupi kehidupan ini walau harus diakui bahwa
bahasa adalah sistem tanda yang paling lengkap dan sempurna. Tanda-tanda itu dapat berupa
gerakan anggota badan, gerakan mata, mulut, bentuk tulisan, warna, bendera, bentuk dan potongan
rumah, pakaian, karya seni: sastra, lukis, patung, film, tari, musik dan lain-lain yang berada di
sekitar kehidupan kita. Dengan demikian, teori semiotik bersifat multidisiplin – sebagaimana
diharapkan oleh Pierce, (2005) agar teorinya bersifat umum dan dapat diterapkan pada segala
macam tanda.
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
25 Universitas Muhammadiyah Kupang
Menurut Pierce,(2005) tanda (representamen) ialah sesuatu yang dapat mewakili sesuatu
yang lain dalam batas-batas tertentu. Tanda akan selalu mengacu ke sesuatu yang lain, oleh Pierce
disebut objek (denotatum). Mengacu berarti mewakili atau menggantikan. Tanda baru dapat
berfungsi bila diinterpretasikan dalam benak penerima tanda melalui interpretant. Jadi interpretant
ialah pemahaman makna yang muncul dalam diri penerima tanda. Artinya, tanda baru dapat
berfungsi sebagai tanda bila dapat ditangkap dan pemahaman terjadi berkat ground, yaitu
pengetahuan tentang sistem tanda dalam suatu masyarakat. Hubungan ketiga unsur yang
dikemukakan Pierce terkenal dengan nama segitiga semiotik. Selanjutnya dikatakan, tanda dalam
hubungan dengan acuannya dibedakan menjadi tanda yang dikenal dengan ikon, indeks, dan simbol.
a. Ikon adalah tanda yang mewakili sumber acuan melalui sebuah bentuk replikasi,
simulasi, imitasi, atau persamaan sebuah tanda di rancang untuk mempresentasikan
sumber acuan melalui simulasi atau persamaan, sebuah tanda yang ada dibuat agar mirip
dengan sumber acuan secara visual.
b. Indeks adalah tanda yang mewakili sumber acuan dengan cara menunjuk padanya atau
mengaitkannya (secara eksplisit atau implisit) dengan sumber acuan lain.
c. Simbol adalah tanda yang mewakili objeknya melalui kesepakatan atau persetujuan
dalam konteks spesifik; makna-makna dalam suatu simbol di bangun melalui
kesepakatan sosial atau melalui beberapa tradisi historis.
2.2 Konsep
2.2.1 Makna
Makna adalah hubungan antara bentuk bahasa dengan objek atau sesuatu (hal) yang
diacunya (Finoza, 2008: 109). Lebih jelas Aristoteles, seorang pemikir Yunani, yang hidup pada
abad ke-3 sebelum Masehi adalah pemikir pertama yang menggunakan istilah makna, beliau
mengatakan bahwa kata sebagai satuan terkecil yang mengandung makna, Aristoteles juga
mengungkapkan bahwa kata itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu kata yang hadir dari kata itu
sendiri secara otonom dan makna kata yang hadir akibat terjadinya hubungan gramatikal (Ulliman
1973: 30). (Plato, 347-429 SM). Dalam bukunya Crathylus, mengungkapkan bahwa bunyi-bunyi
bahasa itu secara implisit mengandung makna-makna tertentu (dalam Sudirman, 2007: 2). Dalam
batasan yang lain Ferdinand de Sausure (1996) memberikan teori tentang tanda / makna yakni
signifie (Inggris signified) yang diartikan dan significant (Inggris; singnifier) yang mengartikan.
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
26 Universitas Muhammadiyah Kupang
Tanda linguistik itu adalah lambang bahasa seperti kata sedangkan yang diartikan/signifie itu adalah
makna (dalam Sudirman, 2007: 2).
Sejalan dengan itu Reising Filosof berkebangsaan Jerman mengungkapkan konsep baru
tentang makna yang diberi nama Gramar, menurut beliau makna dapat di bagi kedalam tiga katagori
yaitu Semasiologi: ilmu tentang tanda, Sintaksis: ilmu tentang kalimat dan Etimologi: ilmu tentang
asal-usul kata serta hubungannya dengan perubahan bentuk maupun perubahan makna (Sudirman,
2007: 2).
Pengertian makna (sense-bahasa Inggris) dibedakan dari arti (meaning-bahasa ingris) itu
sendiri (terutama kata-kata). Sejalan dengan itu, Lyons 1977 menyebutkankan bahwa mengkaji
atau memberikan makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan
hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lain
(Fatimah1999,5).
Dari kajian makna bahasa menurut para ahli di atas berkaitan juga dengan pendapat Wallaco
dan Haafe mengungkapkan bahwa berpikir dengan bahasa, sebenarnya sekaligus melibatkan makna
(Fatimah, 1999: 5).
2.2.2 Kebudayaan
Menurut Koentjaraningrat (1990:15). Menyatakan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa
sansekerta “budayalah” yaitu bentuk jamak dan budi yang berarti “budi atau akal”. Selanjutnya
Rafael Raga Maran (2000:15), menyatakan kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap
masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan. Meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda
dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kebudayaan secara jelas menampakan
kesamaan kodrat manusia dan berbagai suku bangsa dan ras. Mardimin (1994:12). Juga
mendefinisikan kebudayaan yaitu seluruh cara hidup manusia yang dianut bersama-sama dalam
suatu masyarakat guna mencapai suatu taraf hidup yang lebih baik.
Gazabla (1981:147) mengatakan bahwa kehidupan kebudayaan manusia berlangsung dalam
waktu. Manusia mempertahankan diri melalui tradisi atau kebiasaan yaitu dengan mewariskan
unsur-unsurnya dari generasi baik masih dalam bentuk asli maupun bentuk yang sudah berubah
karena terjadi proses perkembangan. Hal ini berarti bahwa maju mundurnya perkembangan suatu
kebudayaan tergantung pada usaha kita menanamkan nilai-nilai luhur budaya tersebut yang perlu
diwariskan.
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
27 Universitas Muhammadiyah Kupang
Manusia pada hakekatnya sebagai mahkluk berbudaya karena perilakunya sebagian besar
dikendalikan oleh budi atau akalnya (Machmoet Effendi 1999:1).Pendapat ini diperkuat dengan
pendapat soekmono (1973) yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta manusia
dan kebudayaan juga mengatur kehidupan manusia itu “manusia dalam kebudayaan itu merupakan
satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, ada manusia ada kebudayaan, sebab tidak ada
kebudayaan jika tidak ada pendukungan yaitu manusia”.
Para ahli Antropologi membagi kebudayaan secara universal dan sekaligus menjadi isi dari
seluruh kebudayaan yang ada di dunia menjadi 7(tujuh) yaitu:
a. Sistem religi dan upacara keagamaan.
b. Sistem dan organisasi kemasyarakatan`
c. Sistem pengetahuan
d. Kesenian
e. Bahasa
f. Sistem mata pencaharian hidup
g. Sistem tehknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 1985:2)
2.2.3 Masyarakat
Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak
merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia. Dalam
ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan
terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat
tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.
Pengertian ini idak merujuk kepada defenisi secara tertutup tetapi lebih kepada kepada
kriteria, agar dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang besar kepada komunitas untuk
melakukan self identification/ mengidentifikasikan dirinya sendiri.
Pengertian Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun
1999 dan masih dipakai sampai saat ini adalah “Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal
usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah
dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang
mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”.
Menurut sumber lain yang disebut sebagai “masyarakat adat” adalah:
1. Penduduk asli (bahasa Melayu: orang asli);
2. Kaum minoritas; dan
3. Kaum tertindas atau termarginal karena identitas mereka yang berbeda dari indentitas yang
dominan di suatu negara atau wilayah.
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
28 Universitas Muhammadiyah Kupang
Secara singkat dapat dikatakan bahwa secara praktis dan untuk kepentingan memahami dan
memaknai Deklarasi ini di lapangan, maka kata “masyarakat adat” dan “masyarakat/penduduk
pribumi” digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama. Pandangan yang sama
dikemukakan dalam merangkum konsep orang-orang suku dan populasi/orang-orang asli dari
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dengan merujuk kepada Konvensi ILO 107 (1957)
dan 169 (1989).
Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (semi
terbuka) dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam
kelompok tersebut.Sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-
entitas. Dengan demikian masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama
lain. Jadi masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu
komunitas yang teratur.
Masyarakat sebagai sekelompok yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga
mereka dapat mengatur diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang telah
dirumuskan atau masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan
dan saling mempengaruhi. Selanjutnya menegaskan bahwa masyarakat adalah sebagai sekelompok
individu yang tersusun mengikuti suatu cara hidup tertentu. Dengan demikian Anderson dan Parker
(Astrid Susanto 1977) mengatakan bahwa masyarakat adalah :
a) Adanya sejumlah orang;
b) Tinggal dalam suatu daerah tertentu;
c) Mengadakan hubungan satu sama lain;
d) Sering terikat satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama;
e) Merupakan suatu kesatuan sehingga mereka mempunyai perasaan solidaritas;
f) Adanya saling ketergantungan;
g) Masyarakat merupakan suatu sistem yang di atur oleh norma-norma, aturan-aturan tertentu;
h) Menghasilakan kebudayaan.
Faktor-faktor yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat antara lain:
a) Adanya dorongan seksual yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunan atau
jenisnya;
b) Adanya kenyataan bahwa manusia itu adalah serba tidak bisa atau sebagai makluk lemah;
c) Kerena terjadinya habit pada tiap-tiap diri manusia bermasyarakat oleh kerena ia telah bisa
mendapatkan bantuan yang berfaedah yang diterima sejak kecil dalam lingkungan;
d) Adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, kesamaan nasib, kesamaan keyakinan atau
cita-cita dan kesamaan kebudayaan.
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
29 Universitas Muhammadiyah Kupang
Dan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mencakup unsur–unsur sebagai
berikut:
a. Manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang menentukan berapa
jumlah manusia tetapi angka minimal ada dua orang.
b. Hidup bersama untuk jangka waktu cukup lama. Hal ini berarti bahwa masyarakat bukanlah
gerombolan orang-orang yang sedang menonton sepak bola.
c. Masyarakat adalah suatu kesatuan dan sistem hidup bersama menimbulkan kebudayaan
demi memudahkan hidupnya.
2.2.4 Pernikahan
Menurut Thalib (1980), mendefenisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk
membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), pernikahan diartikan sebagai
ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan
mmembentuk keluarga (rumah tangga) yang lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.
Berdasarkan pendapat para pakar di atas maka dapat dimpulkan bahwa pernikahan sebagai
ikatan batin antara perempuan dan laki-laki yang hidup bersama dengan tujuan membetuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan sejatera, baik lahir maupun batin dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang maha Esa. Dengan demikian maka pengertian tersebut diatas merupakan konsep
yang memberikan kontribusi pemikiran yang nantinya membawa kita dalam mempelajari tradisi
Makosu dalam upacara pernikahan pada etnis Atoni Meto di Wilayah Amarasi.
2.2.5 Resepsi
Pesta dalam pernikahan biasanya disebut sebagai resepsi, Resepsi merupakan kegiatan suatu
pesta yang dihadiri oleh para undangan atau tamu undangan. Resepsi juga dapat dikatakan sebagai
suatu hal yang menggambarkan keadaan pesta yang dihadiri oleh tamu-tamu tertentu (Purwadi,
2004:127). Dalam pernikahan repsepsi diartikan sebagai wadah atau tempat untuk mengumumkan
bahwa di tempat tersebut sedang berlangsung atau telah terjadi pernikahan suami-istri (Susanto,
2006:108).Resepsi di dalam pernikahan dijadikan seseorang untuk mengucapkan selamat kepada
pasangan baru dan orang tuanya (Purwadi, 2004:127). Resepsi dalam pernikahan atau pun dalam
suatu kagiatan tertentu seperti Konferensi pers perlu pengaturan-pengaturan terlebih dahulu.
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
30 Universitas Muhammadiyah Kupang
2.2.6 Makosu
Menurut masyarakat Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, “Makosu” berasal kata
dasar Kosu yang artinya kaitkan uang di atas kepala, Kosu kemudian membentuk kata kerja dengan
penambahan prefik Ma menjadi “Makosu” yang artinya mengaitkan uang di atas kepala mempelai
wanita.
3.1 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini
digunakan karena penelitian ini menggunakan data deskriptif dengan cara mendeskripsikan sesuatu
yang sudah ada, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian nonstastik. Data dikumpulkan
berupa kata-kata bukan berupa angka. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif.
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Retraen Kecamatan Amarasi selatan Kabupaten
Kupang dengan alasan bahwa Desa Retraen merupakan salah satu wilayah yang memelihara dan
menerapkan tradisi “Makosu” secara turun-temurun. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember
Tahun 2017 sampai bulan Januari Tahun 2018.
3.3 Data dan Sumber Data
Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data gambar berupa foto-foto tentang
“Makosu”, pada acara resepsi pernikahan di Desa Retraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten
Kupang. Sumber data dalam penelitian ini adalah tua-tua adat atau tokoh masyarakat Desa Retraen
Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Ada beberapa teknik dalam penilitian ini diantaranya; 1) teknik observasi; 2) teknik
wawancara; dan 3) dokumentasi.
3.5 Teknik Analisis Data
Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai
berikut: 1) mengidentifikasi data sesuai dengan masalah yang dikaji; 2) menginterpretasi data sesuai
dengan teori yang digunakan; 3) mengklasifikasi data sehingga data-data yang diperoleh yakni data
yang di golongkan ke dalam makna simbolik “makosu”; dan 4) membuat simpulan.
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Bentuk-bentuk “Makosu” dalam Resepsi Pernikahan pada Masyarakat Desa Retraen
Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
31 Universitas Muhammadiyah Kupang
Makosu adalah mengaitkan uang di atas kepala mempelai wanita. Tradisi “Makosu” ini
menjadi aset kebudayaan Masyarakat Desa Retraen secara turun-temurun. Acara ini di lakukan pada
malam resepsi pernikahan pada pembukaan acara hiburan. Tradisi “Makosu” ini dilakukan oleh
keluarga dan undangan untuk mendampingi pasangan dalam tarian “Makosu”. Kedua mempelai
menari dan dikelilingi oleh keluarga dan para undangan pendamping, selanjutnya keluarga dan
undangan bebas memberikan uang kepada kedua mempelai dengan cara uang kertas dijepit dengan
lidi kemudian ditusuk pada sanggul atau ikat kepala kedua mempelai.
Tradisi “Makosu” ini menjadi kebiasaan umum masyarakat Amarasi khususnya Amarasi
Selatan Desa Retraen. Sebagai warisan leluhur maka tarian “Makosu” ini bukan saja memiliki
makna kreatif yang menghibur kedua mempelai atau para undangan, namun secara adat tarian ini
memiliki makna yang sangat berpengaruh bagi masyarakat secara umum terlebih khususnya bagi
kedua mempelai dan keluarganya. Adapun bentuk-bentuk “Makosu” sebagai berikut:
4.2 Pembahasan
4.3.1 Makna Simbolik yang terkandung dalam “Makosu” dalam Resepsi Pernikahan
pada Masyarakat Desa Retraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang
4.3.1.1 Makna Kasih Sayang
Seperti yang diketahui bahwa bentuk “Makosu” pada gambar nomor 2 di atas menunjukan
makna kasih sayang, dimana kedua keluarga yaitu keluarga dari mempelai perempuan dan
mempelai laki-laki masing-masing mengaitkan uang di atas kepala kedua mempelai. Ini bermakna
kasih sayang dimana kedua keluarga memberikan tanda kasih sayang berupa uang sebagai bekal
kepada kedua mempelai dalam menjalani rumah tangga baru.
4.3.1.2 Makna Kekeluargaan
Seperti yang diketahui bahwa bentuk “Makosu” pada gambar nomor 1 di atas menunjukan
makna kekeluargaan, dimana keluarga dari mempelai laki-laki mengaitkan uang di atas kepala
mempelai perempuan. Ini bermakna kekeluargaan dimana keluarga dari mempelai laki-laki
memberikan penghormatan kepada mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayang mereka.
4.3.1.3 Makna Budaya
Gambar Gambar II
I
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
32 Universitas Muhammadiyah Kupang
Seperti yang dilihat pada bentuk gambar “Makosu” nomor 1,2,3 dan 4 di atas merupakan
Makna Budaya. Dimana sebuah tradisi yang secara turun-temurun diwariskan kepada masyarakat di
Amarasi Selatan khusunya Desa Retraen. Tradis “Makosu” ini selalu dilakukan pada saat acara
malam resepsi pernikahan. Selain mengandung makna kasih sayang dan kekeluargaan, “Makosu”
juga mengandung makna budaya yang sangat dalam. Makna budaya yang tersirat adalah sebagai
sebuah penghargaan kepada leluhur. “Makosu” memberi suatu makna yang sangat penting yakni
sebuah relasi yang terjalin bukan saja kepada masyarakat sekarang tetapi juga kepada para leluhur
yang sudah mewariskan budaya “Makosu” tersebut.
5. Penutup
5.1 Simpulan
Tradisi “Makosu” menjadi aset kebudayaan bagi masyarakat Kabupaten Kupang khususnya
wilayah Amarasi secara turun-temurun.Tradisi ini dilakukan pada malam resepsi penikahan pada
pembukaan acara hiburan. Tradisi “Makosu” pada masa kini sudah dikolaborasikan dengan
permainan yang dilakukan oleh undangan dimana undangan disuruh memetik pinang yang sudah
diberi tanda pada beberapa buah, kemudian yang mendapatkan pinang itu akan mendampingi
pasangan dalam tarian “Makosu”. Kedua mempelai menari dan dikelilingi oleh para undangan
pendamping, selanjutnya para undangan bebas memberikan uang kepada kedua mempelai dengan
cara uang kertas dijepit dengan lidi atau kayu kemudian ditusuk pada sanggul atau ikat kepala kedua
mempelai.
Tradisi “Makosu” pada masa kini menjadi kebiasaan umum masyarakat etnis Atoni Meto
Kabupaten Kupang, khususnya di Amarasi Selatan Desa Retraen. Sebagai warisan leluhur, maka
tarian “Makosu” ini bukan saja memiliki makna rekreatif yang menghibur kedua mempelai atau
para undangan, namun secara adat tarian ini memiliki makna yang sangat berpengaruh bagi
masyarakat secara umum terlebih khususnya bagi kedua mempelai dan keluarganya. Tradisi
“Makosu” memiliki makna-makna sebagai berikut: 1) makna kasih sayang , dimana kedua keluarga
yaitu keluarga dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki masing-masing mengaitkan uang
diatas sangkul kedua mempelai: 2) makna kekeluargaan, dimana keluarga dari mempelai laki-laki
mengaitkan uang diatas sangkul mempelai perempuan; 3) makna Budaya, seperti yang dilihat pada
bentuk- bentuk “Makuso” diatas merupakan sebuah tradisi yang secara turun-temurun diwariskan
kepada masyarakat di Amarasi Selatan khusunya Desa Retraen. Tradis “Makosu” ini selalu
dilakukan pada saat acara malam resepsi pernikahan.
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
33 Universitas Muhammadiyah Kupang
5.2 Saran
Ada beberapa saran yang dapat penulis utarakan dalam kaitanya dengan pembahasan
dan hasil analsiis penelitian ini. Berikut beberapa saran yang dapat penulis sajikan: 1) bagi
Masyarakat Kecamatan Amarasi Selatan khususnya Desa Retraen terus menjaga tradisi “Makosu”
peninggalan leluhur secara turun-temurun: 2) bagi pemerintah setempat harus menghimbau kepada
seluruh masyarakat untuk selalu menjaga tradisi “Makosu” supaya jangan ada pengaruh budaya
asing; dan 3) bagi generasi muda untuk belajar tradisi “Makosu” karena secara kenyataan peneliti
melihat bahwa setiap kali melakukan “Makosu” hanya terlihat orang tua saja, tidak terlihat orang-
orang muda melakukan “Makosu”, dengan begitu seiring perkembangan zaman tradisi “Makosu”
ini akan hilang.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Irwan, dkk. 2008. Agama dan kearifan Lokal dalam Tantangan Global.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Andreas Tefa Sawu, "Dawan: Nama Pemberian Orang Lain" dalam Orang Dawan: Beberapa
Catatan Kaki, SKM DIAN Tanggal 12 Juni 1992 dan "Atoni: Nama Pemberian
Sendiri", Dalam Orang Dawan Beberapa Catatan Kaki, SKM DIAN 9 Oktober 1992.
Anton Pain Ratu, Mgr,"Perkawinan Adat Suku Dawan", Dalam SAWI (Sara Karya Perutusan
Gereja), No. 5 Mei 1991, Diterjemahkan Ke Dalam Bahasa Indonesia oleh Bapak
Drs. Antonius Bele.
Barker, Chris. 2004. Cultural Studies.Teori dan Praktik. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Bentang
Pustaka.
---------------. 2005. Cultural Studies. Teori dan Praktik.Penerjemah: Nurhadi. Yogyakarta: Benteng
Pustaka
Barthes, Roland. 1998. The Semiotics Challenge. New York: Hill and Wang.
Berger, Arthur Asa. 2000. Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer. Penerjemah M. Dwi
Marianto dan Sunarto. Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana, buku asli diterbitkan
tahun 1984.
Daud, Haron. 2008. Analisis Data Penelitian Tradisi Lisan Kelantandalam Metodologi Kajian
Tradisi Lisan. (Pudentia, ed.). Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
DEPDIKNAS. 2005. Kamus besar bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
Endraswara, Suwardi. 2003. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta: Yayasan Untuk
Indonesia.
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
ISSN 2656-1980
VOL. 2, No. 2 (2020)
https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/lingko
LINGKO PBSI
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
34 Universitas Muhammadiyah Kupang
Gasabla Sidi, 1981. Perkembangan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Rajawali.
Keraf Goris, 1981.Diksi dan Gaya Bahasa. Ende-Flores: Yayasan Kanisius Arnoldus.
J.G.E Riedel: "Die Landschaft Dawan oder West Timor" Dalam Deutsche
Geographische Blaetter, No. 10/1887.
Liliweri Alo, 2003. Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Buadaya. Yokyakarta: LKIS.
Maran Rafael Raga Maran, 2000.Manusia dan Kebudayaan Dalam perspektif Ilmu Budaya, Jakarta:
Rineka Cipta.
Nazir , Muhamad. 1995. Metode Penelitian. Jakarta: Gahlia Indonesia.
Piet A.Tallo, 1990.OKOMAMA: Simbol Pendekatan Masyarakat Timor. Soe.
Sudikan, Setya Yuwana. 2001. Metode Penelitian Sastra Lisan. Surabaya: Citra Wacana.
Samarin, 1998.Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: Universiti Press.
Soh A.Z dkk, 1994.Upacara Tradisional Daerah NTT. Kupang DEPDIBUD Proyek Infentaris Dan
Dekomptasi Kebudayaan Daerah NTT-Kupang.
Saussure, Ferdinand de. 1998. Pengantar Linguistik Umum. Penerjemah Rahayu S. Hidayat.
Yogyakarta: Gadjahmada University Press, buku asli diterbitkan tahun 1973.
Suan, M. 2011. Atoni Meto Tamolok Uab Meto (Sebuah Makalah Disampaikan Pada Kegiatan
MPAB –AMMPAFA Kupang Pada Tanggal 23 Desember 2011 Di Balai Kusbessi
Desa Benu Kacamatan Takari Kabupaten Kupang.
Sumber: http://forester-untad.blogspot.co.id/2012/11/makalah-tentang-budaya-ritual-upacara.html.
JURNAL LINGKO PBSI Vol. 2 No. 2, 1 AGUSTUS 2020
Ju ©Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kupang
Anda mungkin juga menyukai
- Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaDari EverandSimbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (16)
- 52-Article Text-307-1-10-20181201Dokumen10 halaman52-Article Text-307-1-10-20181201MUHAMMAD AGUS PAMUNGKAS Sastra InggrisBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen15 halaman1 PBAhmadfaril Al AnsyahBelum ada peringkat
- Analisis - Stilistika - Pantun - Upacara - Adat - Perkawinan 33Dokumen14 halamanAnalisis - Stilistika - Pantun - Upacara - Adat - Perkawinan 338ballzBelum ada peringkat
- 1234 Artikel Ruth 11744-11749Dokumen6 halaman1234 Artikel Ruth 11744-11749Dony Alfred NicholasBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen9 halaman1 SMZahra Nur HalisaBelum ada peringkat
- (123dok - Com) Studi Deskriptif Dan Peran Biduan Dalam Pertunjukan Keyboard Erotis Di Kecamatan Bandar Pasir MandogDokumen118 halaman(123dok - Com) Studi Deskriptif Dan Peran Biduan Dalam Pertunjukan Keyboard Erotis Di Kecamatan Bandar Pasir MandogsyalwamaulidaputriBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen11 halaman1 PBMoy LikBelum ada peringkat
- T4-Uas-Semmat-Roy M LomaDokumen11 halamanT4-Uas-Semmat-Roy M LomaRoyBelum ada peringkat
- Jurnal RusliDokumen21 halamanJurnal RusliAslan PutraBelum ada peringkat
- DESAIN PENELITIAN (Terbaru)Dokumen28 halamanDESAIN PENELITIAN (Terbaru)Haryana Suyana4Belum ada peringkat
- Penulisan Ilmiah Tugas 1Dokumen3 halamanPenulisan Ilmiah Tugas 1yomitasonia51Belum ada peringkat
- Proposal BaruDokumen14 halamanProposal BaruTomi Angga CahyadiBelum ada peringkat
- Contoh Skripsi 1Dokumen12 halamanContoh Skripsi 1susantinatalie3Belum ada peringkat
- Tradisi Royong MakassarDokumen12 halamanTradisi Royong MakassarHaryBelum ada peringkat
- Makalah UTS Sistem Sosial Budaya IndonesiaDokumen7 halamanMakalah UTS Sistem Sosial Budaya Indonesiacindy kabnaniBelum ada peringkat
- Eksistensi Kesenian Rebana Gending DesaDokumen9 halamanEksistensi Kesenian Rebana Gending Desaopek betzBelum ada peringkat
- 816 1826 1 PB PDFDokumen11 halaman816 1826 1 PB PDFARISTO MARTIN 2020Belum ada peringkat
- NASKAHDokumen57 halamanNASKAHalfretwedoBelum ada peringkat
- 289 842 1 PBDokumen19 halaman289 842 1 PBCa TasyaBelum ada peringkat
- Template Jurnal MAN Batam - Docx 222Dokumen9 halamanTemplate Jurnal MAN Batam - Docx 222Dava SyafriandanaBelum ada peringkat
- 115 6 PBDokumen112 halaman115 6 PBSiti NurkhalisaBelum ada peringkat
- File Dapus 15Dokumen12 halamanFile Dapus 15allfyn026Belum ada peringkat
- Proposal RiniDokumen53 halamanProposal RiniBonita Silalahi100% (1)
- 913 1661 1 SMDokumen14 halaman913 1661 1 SMDiendra Lintang MahersiBelum ada peringkat
- Proposal Bambu KonsepDokumen22 halamanProposal Bambu KonsepriskiBelum ada peringkat
- Seminar Proposal Bayu PerbataDokumen11 halamanSeminar Proposal Bayu PerbataRhembagBelum ada peringkat
- Bab 1Dokumen30 halamanBab 1Tomi Angga CahyadiBelum ada peringkat
- ID Bahasa Pantun Dalam Makna Dan Budaya MasDokumen86 halamanID Bahasa Pantun Dalam Makna Dan Budaya MasKanjeng DimasBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen22 halaman1 SMSaud M. H. SigalinggingBelum ada peringkat
- Ance MUDRA Vol. 30 Pebruari 2015 - Opt PDFDokumen133 halamanAnce MUDRA Vol. 30 Pebruari 2015 - Opt PDFangelBelum ada peringkat
- Template Jurnal MAN BatamDokumen8 halamanTemplate Jurnal MAN BatamDava SyafriandanaBelum ada peringkat
- Analisis Bentuk Fungsi Dan Makna LelakaqDokumen13 halamanAnalisis Bentuk Fungsi Dan Makna LelakaqBinarKautsarBelum ada peringkat
- Tradisi MamacaDokumen10 halamanTradisi Mamacabahrur rosiBelum ada peringkat
- OhDokumen22 halamanOhWahyuda Mandala Putra A1Belum ada peringkat
- Skripsi Tanpa PembahasanDokumen59 halamanSkripsi Tanpa Pembahasanmanikalbert6Belum ada peringkat
- Kasus SSBIDokumen7 halamanKasus SSBIchriswiaBelum ada peringkat
- 239-Article Text-444-1-10-20170113Dokumen16 halaman239-Article Text-444-1-10-20170113Baiq Sri AndrianiBelum ada peringkat
- TA Semiotika Sem4Dokumen15 halamanTA Semiotika Sem4vikyzabinoxcxBelum ada peringkat
- Pola Komunikasi Kekerabatan Suku Batak Dalam PenggDokumen8 halamanPola Komunikasi Kekerabatan Suku Batak Dalam Penggsiti erikaBelum ada peringkat
- Sasonggan Kajian Bentuk Dan Fungsi Dalam Budaya Berbahasa Bali PDFDokumen15 halamanSasonggan Kajian Bentuk Dan Fungsi Dalam Budaya Berbahasa Bali PDFIKIP PGRI Bali0% (1)
- 12 Maslan 106 113Dokumen8 halaman12 Maslan 106 113chevy rustiawatiBelum ada peringkat
- 1514 4193 1 PBDokumen19 halaman1514 4193 1 PBNursakiaBelum ada peringkat
- Makna Idiomatis Dalam Peribahasa Sunda Perilaku KaDokumen13 halamanMakna Idiomatis Dalam Peribahasa Sunda Perilaku Kaf4844419Belum ada peringkat
- Membangun Kebudayaan Dan Kepribadian ComDokumen20 halamanMembangun Kebudayaan Dan Kepribadian ComAPRIANA CARVALHOBelum ada peringkat
- Analisis Pentingnnya Andung-Andung Terhadap Nilai-Nilai PancasilaDokumen4 halamanAnalisis Pentingnnya Andung-Andung Terhadap Nilai-Nilai PancasilaDosmaria MaringgaBelum ada peringkat
- Umar Kayam0Dokumen8 halamanUmar Kayam0rizkaamirul123Belum ada peringkat
- Bunga Rampai Budaya Sumatera Selatan Budaya Basemah Di Kota Pagar Alam by Rois Leonard Arios, Ernatip, RefisrulDokumen238 halamanBunga Rampai Budaya Sumatera Selatan Budaya Basemah Di Kota Pagar Alam by Rois Leonard Arios, Ernatip, RefisrulhieronimusBelum ada peringkat
- Uas AntropDokumen7 halamanUas AntropKahfindo AryaBelum ada peringkat
- Tradisi Lisan 1Dokumen9 halamanTradisi Lisan 1RutzendBelum ada peringkat
- Suku Bugis MakassarDokumen21 halamanSuku Bugis Makassarputri auliahhfBelum ada peringkat
- 8-Article Text-723-1-10-20210604Dokumen12 halaman8-Article Text-723-1-10-20210604Ana Uswatun KhasanahBelum ada peringkat
- I1B113009 - ArtikelDokumen5 halamanI1B113009 - ArtikelwndisandraBelum ada peringkat
- Jurnal KebudayaanDokumen6 halamanJurnal KebudayaanDwi CahyaniBelum ada peringkat
- MINI RISET Isb Rijal Lumban RajaDokumen8 halamanMINI RISET Isb Rijal Lumban Rajapakpak chanelBelum ada peringkat
- 1479-File Utama Naskah-3225-1-10-20220328Dokumen6 halaman1479-File Utama Naskah-3225-1-10-20220328Ahmad RiyadiBelum ada peringkat
- Bab IDokumen28 halamanBab IJunaidi MesakBelum ada peringkat
- Moh. Amar Rizqi Essay Bi 2Dokumen2 halamanMoh. Amar Rizqi Essay Bi 2RzxyyBelum ada peringkat
- 2296 6236 1 PBDokumen12 halaman2296 6236 1 PBmariowara83100% (1)
- Semiotik Dan Dinamika Sosial Budaya - Mengenang Prof. Dr. Benny H. Hoed, Bapak Semiotik Indonesia PDFDokumen156 halamanSemiotik Dan Dinamika Sosial Budaya - Mengenang Prof. Dr. Benny H. Hoed, Bapak Semiotik Indonesia PDFLis SugiantoroBelum ada peringkat