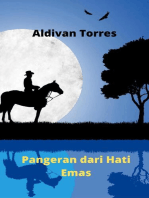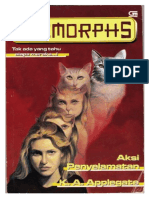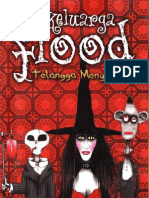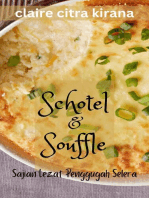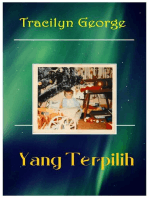Kisah Klan Otori IVThe Harsh Cry of The Heron
Diunggah oleh
Sir-Nala Newgram100%(1)100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
169 tayangan1.053 halamanIndonesia
Judul Asli
KisahKlanOtoriIVTheHarshCryOfTheHeron
Hak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniIndonesia
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
100%(1)100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
169 tayangan1.053 halamanKisah Klan Otori IVThe Harsh Cry of The Heron
Diunggah oleh
Sir-Nala NewgramIndonesia
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 1053
for J
KISAH KLAN OTORI:
THE HARSH CRY OF THE HERON
Copyrigth@Lian Hearn Associates Pty Ltd 2006
All rights reserved
Hak terjemahan ada pada Penerbit Matahati
Diterbitkan oleh Penerbit Matahati
email: info@penerbitmatahati.com
website: www.penerbitmatahati.com
Penerjemah: Febry E.S.
Penyuming: Miq Acango
Tata letak: CaderaDesign
Korektor: Djohan Suryana
Cetakan pertama: Desember 2006
Cetakan kedua: Januari 2007
Cetakan ketiga: Februari 2007
Cetakan keempat: Februari 2008
Judul asli:
TALES OF THE OTORI:
The Harsh Cry of the Heron
by Lian Hearn
Simbol Klan oleh Claire Aher
Terjemah Tales of the Heiki adalah dari Helen
Craig McCullough, dan diterbitkan oleh Stanford
University Press, 1988
Ebook (PDF) by
syauqy_arr@yahoo.co.id
Weblog, http://hanaoki.wordpress.com
Dentang genta Gion Shoja
mengumandangkan ketidakabadian
segalanya.
Warna bunga sala mengungkapkan
kebenaran bahwa kemakmuran akan
mengalami kemunduran.
Keangkuhan tak akan bertahan lama,
layaknya mimpi di malam musim
semi
Kekuasaan pada akhirnya akan jatuh,
layaknya debu yang tertiup angin.
THE TALE OF THE HEIKI
THE HARSH CRY
OF THE HERON
TOKOH UTAMA
Otori Takco .................... penguasa Tiga Negara
Otori Kaede ....................................... istrinya
Shigeko .... putri sulung mereka, pewaris Maruyama
Maya
Miki
Arai Zenko ........... pemimpin Klan Arai, penguasa
Kumomoto
Arai Hana............................ istrinya, adik Kaede
Sunaomi
Chikara
Muto Kenji ......... ketua keluarga Muto dan Tribe
Muro Shizuka .......... pengganti dan keponakan
Kenji, ibu dari Zenko dan Taku
Muto Taku ........................... mata-mata Takeo
Sada......................... anggota Tribe sahabat Maya
Mai ............................................ adik dari Sada
Yuki (Yusetyu)............ putri Kenji, ibu dari Hisao
Muto Yasu .................................... pedagang
}
.. putri kembar mereka
}
.. putra mereka
Imai Bunta ........................... informan Shizuka
Tabib Ishida ........ suami Shizuka, tabibnya Takco
Sugita Hiroshi........... pengawal senior Maruyama
Miyoshi Kahei............... panglima perang Takeo,
penguasa Yamagata
Miyoshi Gemba.............................. saudaranya
Sonoda Mitsuru ................... penguasa Inuyama
Ai........................................ istrinya, adik Kaede
Matsuda Shingen............ Kepala biara Terayama
Kubo Makoto (Eiken)................ penggantinya,
sahabat Takeo
Minoru..................................... jurutulis Takeo
Kurado Junpei
Kurado Shinsaku
Terada Fumio .............. pemimpin angkatan laut
Lord Kono ......................... putra Lord Fujiwara
Saga Hideki .............................. jenderal Kaisar
Don Joao ......................... orang asing, pedagang
Don Carlo ......................... orang asing, pendeta
Madaren ............................. penerjemah mereka
Kikuta Akio ..................... ketua keluarga Kikuta
Kikuta Hisao ........................ anaknya Kikuta
Gosaburo ..................................... paman Akio
... pengawal Takeo
}
KUDA
Tenba ............ kuda hitam pemberian Shigeko
untuk Taeko
Dua anak Raku, surai dan ekor mereka berwarna abu-
abu
Ryume............................ kuda tunggangan Taku
Keri ............................ kuda tunggangan Hiroshi
Ashiege ....................... kuda tunggangan Shigeko
"Cepat kemari! Ayah dan Ibu sedang
bertarung!" Otori Takeo mendengar putrinya
memanggil adik-adik-nya dari kediaman
mereka di kastil Inuyama, dengan cara yang
sama ia mendengarkan semua hiruk-pikuk
baik di dalam kastil dan juga dari kota di luar
kastil. Namun dia mengabaikan suara-suara
itu, sama seperti ia mengabaikan nyanyian
yang mengalun dari nightingale floor di
bawah kakinya. Ia hanya berkonsentrasi pada
lawannya: Kaede, istrinya.
Mereka bertarung menggunakan tongkat:
ia memang lebih tinggi, tapi istrinya terlahir
kidal dan mampu menggunakan tangan
kanan dengan sama baiknya. Sementara jari
tangan kanannya putus karena tebasan belati
bertahun-tahun lalu dan harus belajar meng-
gunakan tangan kiri.
Saat ini hari terakhir di tahun ini, hawa
dingin menusuk, langit pucat kelabu,
matahari musim dingin meredup. Mereka
sering berlatih dengan cara ini di musim
dingin: menghangatkan tubuh dan membuat
sendi-sendi tetap lentur, dan Kaede suka
putri-putrinya melihat bagaimana perem-
puan mampu bertarung layaknya laki-laki.
Ketiga putri mereka berlarian: Shigeko, si
sulung. yang akan berusia lima belas lahun
pada tahun baru ini, kedua adiknya tiga belas
tahun. Papan lantai melantunkan nyanyian
di bawah langkah kaki Shigeko, tapi si
kembar menjejakkan kaki mereka begitu
ringan dengan cara Tribe. Mereka sudah
sering berlarian melintasi nightingale floor
sejak kecil, dan tanpa menyadari belajar
untuk membuatnya tidak bersuara.
Kepala Kaede ditutupi selendang sutra
merah yang dililitkan menutupi wajahnya,
maka Takeo hanya bisa melihat matanya.
Mata yang penuh dengan energi bertarung,
dan gerakan-gerakannya masih cepat serta
kuat. Sulit dipercaya Kaede adalah ibu dari
tiga anak: dia masih bergerak dengan
kekuatan dan kebebasan seorang gadis.
Serangannya membuat Takeo menyadari
akan usia dan kelemahan fisiknya. Hentakan
serangan Kaede pada tongkat miliknya mem-
buat tangannya terasa nyeri.
"Aku mengaku kalah," ujar Takeo.
"Ibu menang!" seru ketiga putrinya
dengan bangga. Shigeko lari menghampiri
ibunya dengan membawa handuk. "Untuk
sang pemenang," ujarnya seraya mem-
bungkuk dan menyodorkan handuk dengan
dua tangan.
"Kita harus bersyukur karena hidup dalam
damai," tutur Kaede, seraya tersenyum dan
menyeka wajahnya. "Ayah kalian belajar
keahlian berdiplomasi dan tak perlu lagi ber-
tarung mempertaruhkan nyawanya!"
"Setidaknya kini aku sudah mendapat
peringatan!" sahut Takeo, memberi isyarat
pada salah satu penjaga, yang tengah
menyaksikan dari taman untuk mengambil
longkatnya.
"Ijinkan kami bertarung melawan Ayah!"
ujar Miki, si bungsu, dengan nada me-
mohon. Dia berjalan ke tepian beranda dan
mengacungkan kepalan tangan ke arah ayah-
nya. Takeo berhati-hati untuk tidak menatap
langsung mata atau menyentuh putrinya itu
selagi memberikan tongkatnya.
Takeo sadar akan rasa enggan dalam diri-
nya. Bahkan orang dewasa dan prajurit
tangguh sekalipun, takut pada si kembar
bahkan, batinnya dengan hati pilu, ibunya
sendiri juga takut.
"Ayah ingin lihat apa saja yang telah
dipelajari Shigeko," sahutnya. "Kalian berdua
boleh menjajal kebolehannya."
Selama beberapa tahun putri sulungnya
menghabiskan sebagian besar waktu di
Terayama, di bawah pengawasan mantan
Kepala Biara, Matsuda Shingen, mantan
guru Takeo, untuk mempelajari Ajaran
Houou. Shigeko tiba di Inuyama sehari
sebelumnya, untuk merayakan Tahun Baru
bersama keluarganya, juga perayaan me-
masuki usia akil balik. Kini Takeo memer-
hatikan putrinya selagi mengambil tongkat
yang tadi digunakannya serta meyakinkan
kalau Miki menggunakan tongkat yang lebih
ringan. Secara fisik, Shigeko mirip ibunya:
bentuk tubuh ramping yang sama serta
kerapuhan yang jelas terlihat, namun me-
miliki karakter, berpengetahuan luas berkat
latihan dan pengalaman, periang serta tegas
dan tidak mudah berubah pendirian. Ajaran
Houou amat keras dalam pengajarannya, dan
guru-gurunya tidak membuat pengecualian
untuk usia dan jenis kelamin, namun ia tetap
menerima ajaran dan latihan yang diberikan,
hari-hari panjang dalam kesendirian serta
kcsunyian, dengan sepenuh hati. Dia ke
Terayama atas kemnuannya sendiri, karena
Ajaran Houou merupakan ajaran jalan
kedamaian, dan sejak kecil Shigeko telah
diajarkan ayahnya tentang pandangan untuk
mewujudkan wilayah yang damai tempat
kekcrasan tak pernah merajalela.
Cara bertarungnya agak berbeda dari cara
yang diajarkan kepada Takeo, dan dia sangat
suka memerhatikan putrinya itu, menikmati
bagaimana gerakan-gerakan tradisional
menyerang diubah menjadi gerakan beladiri,
dengan tujuan melemahkan lawan tanpa
menyakiti.
"Jangan curang," kata Shigeko pada Miki,
karena si kembar memiliki semua
kemampuan Tribebahkan lebih, Takeo
curiga. Saat ini, kemampuan mereka ber-
kembang pesat, dan meskipun dilarang
menggunakannya dalam kehidupan sehari-
hari, terkadang godaan untuk memper-
mainkan guru-guru serta mengelabui para
pelayan sulit untuk dibendung.
"Mengapa aku tidak boleh memperlihat-
kan apa yang sudah kupelajari?" tanya Miki,
karena dia juga baru kembali dari
pelatihandi desa Tribe bersama keluarga
Muto. Kakaknya Maya akan kembali ke sana
setelah perayaan. Akhir-akhir ini jarang sekali
seluruh anggota keluarga bisa berkumpul
bersama: pendidikan yang berbeda bagi tiap
anak, tuntutan pada orangtua untuk mem-
beri perhatian yang sama besarnya untuk
seluruh Tiga Negara berarti perjalanan tanpa
henti serta sering berjauhan. Tuntutan dalam
pemerintahan kian meningkat: perundingan
dengan orang asing; penjelajahan dan per-
dagangan; pengembangan persenjataan;
pengawasan distrik lokal yang mengatur
sendiri administrasinya; percobaan pertanian;
impor perajin asing dan teknologi baru;
pengadilan untuk mendengarkan keluhan
serta ketidakpuasan. Takeo dan Kaede
memikul beban ini bersama. Kaede lebih
banyak menangani wilayah Barat, sedang
Takeo Negara Tengah dan keduanya bekerja-
sama menangani wilayah timur, tempat adik
Kaede, Ai beserta suaminya, Sonoda Mitsuru,
memegang bekas wilayah Tohan.
Miki setengah kepala lebih pendek dari
kakaknya, tapi sangat kuat dan cepat;
Shigeko tampak nyaris tak mampu meng-
imbangi gerakannya, tapi adiknya tak
mampu menembus pertahanannya. Dalam
beberapa saat Miki sudah kehilangan
tongkatnya, yang tampak seperti terbang
melayang dari jemarinya, dan sewaktu
tongkat itu membumbung tinggi Shigeko
menangkapnya dengan mudah.
"Kau curang!" Miki terengah-engah.
"Lord Gemba yang mengajari," sahut
Shigeko dengan bangga.
Adik kembarnya yang satu lagi, Maya,
mengambil giliran selanjutnya juga kalah
dengan cara yang sama.
Shigeko berkata, pipinya bersemu merah,
"Ayah, ayo bertarung denganku!"
"Baiklah," Takeo setuju karena terkesan
dengan apa yang telah dipelajari putrinya dan
ingin tahu sampai di mana kemampuannya
menghadapi ksatria yang terlatih.
Takeo menyerang putrinya dengan cepat,
tanpa menahan tenaga, dan serangan pertama
mengejutkan gadis itu. Tongkat ayahnya
mengenai dadanya; Takco menahan
tikamannya agar tidak menyakiti putrinya.
"Jika ini pedang, nyawamu pasti sudah
melayang," ujarnya.
"Lagi," sahut Shigeko dengan tenang, dan
kali ini siap bersiap menghadapi serangan
yang akan dilancarkan ayahnya; bergerak
dengan kecepatan tanpa banyak tenaga,
mengelak dari dua pukulan dan berhasil
masuk ke sisi kanan ayahnya tempat tangan
yang lebih lemah, menghentak sedikit, cukup
untuk menggoyahkan keseimbangan ayah-
nya, kemudian meliukkan tubuhnya.
Tongkat milik Takeo jatuh ke tanah.
Didengarnya helaan napas si kembar, dan
para penjaga terperangah.
"Bagus sekali," ujarnya.
"Ayah tidak berusaha sekuat tenaga," sahut
Shigeko kecewa.
"Tentu saja ayah berusaha sekuat tenaga.
Sama kuatnya seperti yang pertama tadi.
Tapi, ayah sudah dibuat lelah oleh ibumu,
juga karena sudah tua dan tidak sekuat dulu
lagi!"
"Tidak," pekik Maya. "Shigeko menang!"
"Tapi itu sama saja kau curang," timpal
Miki dengan serius. "Bagaimana kau melaku-
kannya?"
Shigeko tersenyum, menggelengkan
kepala. "Itu yang harus kau lakukan dengan
pikiran, jiwa serta tangan di saat bersamaan.
Butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa
menguasainya. Aku tidak bisa memperlihat-
kannya begitu saja pada kalian."
"Kau melakukannya dengan sangat baik,"
ujar Kaede. "Aku bangga." Nada suaranya
terdengar penuh kasih sayang dan
kekaguman, seperti biasa hanya tertuju pada
putri sulungnya.
Si kembar saling benukar pandang.
Mereka iri, pikir Takeo. Mereka tahu
ibunya tidak memiliki kasih sayang yang
sama kuatnya pada mereka. Dan dirasakan-
nya debaran perasaan ingin melindungi yang
tak asing lagi atas kedua putri kembarnya.
Sepertinya ia selalu berusaha menjauhkan
mereka dari segala yang bahayasejak
mereka lahir, ketika Chiyo ingin menyingkir-
kan bayi kedua, Miki, lalu membiarkannya
mati. Ini tindakan yang biasa lakukan pada
anak kembar karena anak kembar dianggap
tidak wajar bagi manusia, membuat mereka
kelihatan lebih mirip hewan, kucing atau
anjing.
"Mungkin tampak kejam bagi Anda, Lord
Takeo," Chiyo memeringatkannya. "Tapi
lebih baik bertindak sekarang daripada
menanggung malu dan sial, sebagai ayah dari
anak kembar, rakyat akan percaya kalau
Anda menjadi sasarannya."
"Bagaimana mereka bisa berhenti percaya
pada takhayul dan kekejaman semacam itu
bila bukan kita yang memberi contoh?"
sahutnya dengan gusar karena bagi orang
yang terlahir di kalangan kaum Hidden, ia
sangat menghargai nyawa manusia lebih dari
apa pun, dan tak percaya kalau memper-
tahankan nyawa anak akan mendatangkan
hinaan atau nasib buruk.
Kemudian ia terkejul oleh kekuatan
takhayul ini. Kaede pun bukannya tidak ter-
pengaruh, dan sikapnya pada putri kembar-
nya menggambarkan kegelisahannya yang
bercabang. Dia lebih memilih mereka tinggal
terpisah, satu atau yang lainnya biasanya
tinggal bersama Tribe; dan Kaede tak meng-
inginkan kehadiran mereka saat perayaan
usia akil balik sang kakak, takut kalau
kehadiran mereka akan mendatangkan nasib
sial bagi Shigeko. Tapi Shigeko, yang sama
protektifnya terhadap si kembar seperti ayah-
nya, memaksa mereka harus hadir. Takeo
senang dengan hal itu, tidak ada yang lebih
membahagiakan selain melihat semua
anggota keluarga berkumpul bersama, berada
dekat dengannya. Dipandanginya mereka
semua dengan penuh kasih sayang, dan sadar
kalau perasaan itu diambil alih oleh sesuatu
yang lebih menggairahkan: hasrat untuk ber-
baring bersama dan merasakan kulit istrinya.
Pertarungan tongkat tadi telah membangkit-
kan kenangannya saat pertama kali jatuh
cinta pada Kaede, pertama kali mereka
bertanding di Tsuwano sewaktu ia masih
berusia tujuh belas tahun sedangkan Kaede
lima belas tahun. Adu tanding itu ber-
langsung di Inuyama, tepat di tempat yang
sama hari ini, untuk pertama kalinya mereka
tidur bersama, terdorong hasrat yang timbul
dari keputusasaan juga kesedihan. Rumah
yang lama, kastil milik Iida, nightingale floor
yang pertama habis terbakar ketika Inuyama
jatuh namun Arai Daiichi membangunnya
kembali dengan cara yang hampir sama, dan
kini menjadi salah satu dari Empat Kota yang
termasyhur di penjuru Tiga Negara.
"Anak-anak harus segera beristirahat," ujar
Takeo, "karena perayaan di biara dimulai
tengah malam, lalu ada Jamuan Makan
Tahun Baru. Acara baru akan selesai pada
Waktu Macan*. Aku juga ingin berbaring
sebentar."
"Akan kuminta agar tungku disiapkan di
kamar," sahut Kaede, "sebentar lagi aku akan
* Waktu Macan: berkisar antara jam 01.00 s/d
jam 03.00. [peny]
bergabung denganmu."
***
Sinar matahari telah memudar saat Kaede
mendatangi Takeo, dan malam musim
dingin mulai menjelang. Meskipun ada
tungku, hembusan napas Kaede membentuk
kabut putih di tengah dinginnya udara.
Selesai mandi, aroma kulit padi dan aloe dari
air masih melekat di kulitnya. Di balik jubah
tebal musim dingin tubuhnya terasa hangat.
Takeo melepas sabuk istrinya lalu
menyelinakan tangan ke balik pakaiannya,
menarik tubuh Kaede agar berdekatan
dengannya. Kemudian dilepasnya syal yang
menutupi kepala Kaede lalu menarik, meng-
usapkan tangannya di atas kulit lembut ber-
bulu halus.
"Jangan," ujar Kaede. "Buruk sekali."
Takeo tahu kalau istrinya tak rela kehilangan
rambut panjangnya yang indah, maupun
bekas luka di tengkuk lehernya yang putih,
yang mencoreng kecantikan yang pernah
menjadi legenda sekaligus takhayul; tapi
tidak nampak olehnya ketidaksempumaan
tubuh istrinya, yang tampak hanyalah makin
bertambahnya kerapuhan yang justru di
matanya membuat sang istri semakin terlihat
memesona.
"Aku menyukainya. Seperti pemain
sandiwara. Membuatmu kelihatan seperti
laki-laki sekaligus perempuan, juga orang
dewasa sekaligus anak-anak."
"Kau juga harus perlihatkan bekas luka-
mu." Kaede menarik sarung tangan sutra
yang biasa dikenakan Takeo di tangan
kanannya, lalu membawa sisa bekas jarinya
yang putus ke bibirnya. "Apakah tadi aku
menyakitimu?"
"Tidak juga. Hanya sisa rasa sakit
pukulan seperti apa pun menyakitkan
persendian dan membangkitkan rasa sakit-
nya." Takeo bicara lagi dengan suara pelan,
"Saat ini aku merasa kesakitan, tapi karena
alasan lain."
"Rasa sakit semacam itu bisa kusembuh-
kan," bisik Kaede, seraya menarik tubuh
suaminya, membuka diri pada Takeo,
membawanya memasuki dirinya, memper-
temukan hasrat mereka.
"Kau selalu menyembuhkan diriku," ujar
Takeo kemudian. "Kau membuat diriku
utuh."
Kaede berbaring dalam dekapan Takeo,
dengan kepala bersandar di bahunya.
Pandangannya menjelajahi setiap sudut
kamar. Cahaya lampu bersinar dari pegangan
best, tapi di balik daun penutup jendela
langit tampak kelam.
"Mungkin tadi kau sudah memberiku
seorang putra," ujar Kaede, tidak mampu
menyembunyikan kerinduan dalam nada
suaranya.
"Kuharap tidak!" seru Takeo. "Dua kali
hamil nyaris merenggut nyawamu. Lagipula
kita tidak perlu anak laki-laki," imbuhnya
dengan ringan. "Kita sudah punya tiga anak
perempuan."
"Aku pernah mengatakan hal yang sama
pada ayahku," aku Kaede. "Aku percaya
kalau diriku bernilai sama dengan laki-laki."
"Begitu pula dengan Shigeko," sahut
Takeo. "Dia akan mewarisi Tiga Negara,
juga anak-anaknya kelak."
"Anak-anaknya! Shigeko masih anak-anak.
tapi sudah cukup dewasa untuk ditunangkan.
Siapa orang yang bisa kita calonkan dengan-
nya?"
"Jangan terburu-buru. Shigeko seperti
piala, perhiasan yang nyaris tak ternilai
harganya. Kita takkan melepasnya dengan
percuma."
Kaede kembali pada pokok pembicaraan
sebelumnya seolah hal itu menggerogoti
dirinya. "Aku ingin memberimu anak laki-
laki."
"Meskipun dengan adanya pewarisanmu
sendiri serta contoh dari Lady Maruyama!
Kau masih saja bicara layaknya putri dari
keluarga ksatria!"
Kegelapan dan ketenangan membawa
Kaede menyuarakan kecemasannya lebih
jauh lagi. "Kadang aku berpikir si kembar
menutup rahimku. Aku merasa andai mereka
tidak dilahirkan aku akan dikaruniai anak
laki-laki."
"Kau terlalu banyak mendengar takhayul!"
"Mungkin kau benar. Tapi apa yang akan
terjadi pada anak kembar kita? Mereka tidak
bisa mewarisi, kalau-kalau terjadi sesuatu
pada Shigeko, semoga Surga tidak mem-
biarkan itu terjadi. Maka siapa yang akan
dinikahkan? Tidak satu pun keluarga
bangsawan atau ksatria mau menerima si
kembar, terutama yang ternodamaaf
oleh darah Tribe serta kemampuan yang
mirip ilmu sihir."
Takeo tak bisa menyangkal bahwa hal
yang sama juga mengganggu pikirannya,
namun ia berusaha menyingkirkannya. Putri
kembarnya masih amat muda: siapa yang
tahu apa yang disiapkan nasib untuk mereka?
Setelah beberapa saat, Kaede berkata
pelan, "Tapi mungkin kita memang sudah
terlalu tua. Semua orang penasaran mengapa
kau tidak mengambil istri muda, atau selir,
agar bisa punya lebih banyak anak."
"Aku hanya menginginkan satu istri,"
sahut Takeo dengan sungguh-sungguh.
"Perasaan apa pun yang pernah kuperlihat-
kan untuk berpura-pura, peran apa pun yang
kumainkan, cintaku padamu sederhana dan
sejatj adanyaaku takkan bercinta dengan
siapa pun selain kau. Pernah kukatakan
padamu, aku pernah bersumpah pada
Kannon di Ohama. Aku tidak melanggar
sumpah itu selama enam belas tahun. Dan
aku tak akan melanggamya sekarang."
"Kurasa aku bisa mati cemburu," aku
Kaede. "Namun perasaanku tidaklah penting
dibandingkan kepentingan negara."
"Aku percaya kita dipersatukan dalam
cinta yang merupakan landasan pemerin-
tahan kita yang baik. Aku tak akan merusak-
nya," sahutnya. Takeo merengkuh Kaede
lebih dekat lagi, mengusapkan tangannya di
atas bekas luka leher istrinya, merasakan
tulang rusuk yang mengeras dari jaringan
yang tertinggal bekas luka bakar. "Selama
kita bersatu, negara kita akan tetap damai
dan kuat."
Setengah mengantuk Kaede berkata, "Kau
ingat saat kita berpisah di Terayama? Kau
menatap mataku lalu aku jatuh tertidur. Aku
tidak pernah menceritakan ini padamu. Aku
bermimpi tentang Dewi Putih: dia berbicara
padaku. Bersabarlah, katanya: dia akan
menjemputmu. Kemudian satu kali lagi di
Gua Suci kudengar suaranya mengatakan hal
yang sama. Itu satu-satunya hal yang
membuatku bertahan selama dikurung di
kediaman Lord Fujiwara. Di sana aku belajar
bersabar. Aku terpaksa belajar bagaimana
harus menunggu, tidak melakukan apa-apa,
agar ia tidak punya alasan untuk mencabut
nyawaku, Setelah itu, saat dia mati, satu-
satunya tempat yang terpikir olehku hanya-
lah kembali ke gua suci, kembali pada sang
dewi. Bila kau tidak datang, mungkin aku
akan terus tinggal di sana melayani sang dewi
sepanjang sisa hidupku. Lalu kau datang: aku
melihatmu, begitu kurus, racun masih ber-
sarang di tubuhmu, tangan indahmu hancur.
Aku tak pernah melupakan saat itu; tangan-
mu di atas leherku, salju turun, jeritan pilu
sang bangau...."
"Aku tak layak mendapatkan cintamu,"
bisik Takeo. "Cintamu adalah anugerah
terindah dalam hidupku, dan aku tak bisa
hidup tanpa dirimu. Kau tahu, hidupku di-
bimbing oleh ramalan..."
"Kau pernah bilang. Dan kita sudah
melihatnya terpenuhi: Lima Peperangan,
campur tangan Surga "
Akan kuceritakan sisanya sekarang, pikir
Takeo. Akan kukatakan mengapa aku tidak
menginginkan anak laki-laki, karena si
peramal buta itu mengatakan hanya putraku
yang bisa membawa kematian padaku. Akan
kukatakan padanya tentang Yuki, dan anak
yang dilahirkannya, putraku, yang kini
berusia enam belas tahun.
Namun ia tak ingin menyakiti istrinya.
Untuk apa mengorek-ngorek masa lalu? Lima
pertempuran telah menjadi bagian dari
mitologi Otori, walaupun Takeo sadar hahwa
ia yang memilih bagaimana menghitung
semua pertempuran itu: bisa saja jumlah
mencapai enam, empat atau tiga. Kata-kata
bisa diubah dan dimanipulasi agar terkesan
sarat makna. Bila suatu ramalan dipercaya,
seringkali terpenuhi. Maka ia takkan
mengeluarkan ramalan yang satu itu dalam
kata-kata, karena dengan begitu justru meng-
hidupkan ramalan itu.
Dilihatnya Kaede hampir tertidur. Terasa
hangat di bawah selimut, meskipun udara di
wajahnya terasa dingin menusuk. Tak lama
lagi ia sudah harus bangun, mandi serta ber-
pakaian resmi dan menyiapkan diri untuk
upacara menyambut datangnya Tahun Baru.
Malam ini akan jadi malam yang panjang.
Tubuhnya mulai terasa rileks, dan akhirnya
ia pun tertidur.*
Ketika putri Lord Otori senang jalan ke kuil
di Inuyama karena terdapat deretan patung
anjing putih yang diselingi deretan batu
tempat ratusan lampu dinyalakan di malam-
malam perayaan besar. Kelap-kelip cahaya
lampu menyinari patung-patung anjing
hingga terlihat hidup. Udara cukup dingin
hingga membuat wajah, jari tangan, dan kaki
mati rasa, dan penuh dengan asap serta
aroma dupa dan kayu pinus yang baru
ditebang.
Para peziarah pertama di Tahun Baru ini
berkerumun di anak tangga curam menanjak
menuju kuil. Lonceng besar berdentang,
membuat Shigeko bergidik. Ibunya berada
beberapa langkah di depan, berjalan ber-
dampingan dengan Muto Shizuka, pen-
damping kesayangannya. Suami Shizuka,
tabib Ishida, sedang ke daratan utama. Sang
tabib diperkirakan takkan kembali hingga
musim semi. Shigeko senang Shizuka akan
bersama mereka selama musim dingin karena
dia salah satu dari sedikit orang yang di-
hormati si kembar; dan Shigeko pikir,
Shizuka pun menyayangi dan memahami
mereka berdua.
Si kembar berjalan mengapit Shigeko;
sesekali beberapa orang dari kerumunan yang
berada di sekeliling mereka menatap lalu
menjauh, tak ingin tersentuh; tapi umumnya
mereka tidak terlalu jelas terlihat di bawah
sinar remang-remang.
Shigeko tahu para penjaga ada di depan
dan belakang mereka, dan putra Shizuka,
Taku, bertugas menjaga ayahnya. Ia tahu
kalau Shizuka dan ibunya membawa pedang
pendek, dan ia pun menyembunyikan sebuah
tongkat di balik jubahnya. Ia selalu mem-
bawa tongkat karena berguna untuk me-
lumpuhkan orang tanpa membunuh, seperti
yang diajarkan Lord Miyoshi Gemba, salah
seorang gurunya di Terayama. Setengah
berharap ia akan sempat mencobanya, tapi
sepertinya mereka takkan diserang di jantung
Inuyama.
Namun ada sesuatu di malam ini yang
membuatnya waspada: bukankah guru-
gurunya sering mengatakan bahwa ksatria
harus selalu siaga agar kematian, baik
kematian dirinya maupun lawannya, bisa
terhindar?
Mereka tiba di aula utama kuil, tempat
Shigeko bisa melihat ayahnya yang tampak
kerdil di antara atap tinggi dan patung
raksasa dewa-dewa langit. Sulit dipercaya
orang yang duduk resmi di depan altar
adalah orang yang bertarung dengannya sore
tadi di atas nightingale floor. Rasa sayang dan
hormat yang mendalam pada ayahnya
mengalir dalam diri Shigeko.
Setelah mempersembahkan sesajian dan
berdoa di depan Sang Pencerah, para
perempuan berjalan ke kiri lalu berjalan lebih
tinggi ke arah gunung menuju ke kuil sang
maha pengampun, Kannon. Di sini para
penjaga tetap berada di luar gerbang karena
hanya perempuan yang diijinkan masuk ke
pelataran.
Ketika Shigeko berlutut di atas anak
tangga kayu di depan patung yang berkilat,
Miki menyentuh lengan kakaknya.
"Shigeko," bisiknya. "Apa yang dilakukan
laki-laki itu di sini?"
"Di sini itu di mana?"
Miki menunjuk ke ujung beranda, tempat
seorang perempuan muda berjalan ke arah
mereka dengan membawa semacam
bingkisan: perempuan itu berlutut di
hadapan Kaede lalu mengulurkan nampan-
nya.
"Jangan disentuh!" seru Shigeko. "Miki,
ada berapa orang?"
"Dua," jerit Miki. "Dan mereka membawa
belati!"
Saat itulah Shigeko melihat dua orang itu
muncul dari udara, melompat ke arah
mereka. Shigeko berteriak memeringatkan
sambil mengeluarkan tongkatnya.
"Mereka ingin membunuh Ibu!" pekik
Miki.
Tapi Kaede telah siaga pada seruan
Shigeko yang pertama. Pedang sudah di
tangannya. Gadis itu melempar nampan di
depannya sambil menarik senjata miliknya,
tapi Shizuka yang juga bersenjata, mem-
belokkan serangan pertama, mematikan
serangan gadis itu dengan membuat senjata-
nya melayang di udara, kemudian berbalik
menghadapi para penyerang laki-laki. Kaede
mendekati perempuan itu dan meng-
hempaskannya ke tanah, seraya mengunci
lengannya.
"Maya, di dalam mulutnya," seru Shizuka.
"Jangan biarkan dia menelan racunnya."
Perempuan itu melancarkan serangan dan
tendangan, tapi Maya dan Kaede membuka
paksa mulutnya dan Maya memasukkan jari
ke dalam mulut, mencari-cari pil beracun
lalu mengeluarkannya.
Sabetan pedang Shizuka melukai salah satu
penyerang laki-laki, dan darahnya berceceran
di atas anak tangga dan di lantai. Shigeko
memukul penyerang yang satunya lagi di
bagian samping lehernya, seperti yang pernah
dicontohkan Gemba, dan selagi si penyerang
itu terhuyung, dihujamkannya tongkat ke
arah selangkangannya, tepat ke bagian alat
vitalnya. Tubuhnya melekuk, muntah karena
kesakitan.
"Jangan bunuh mereka,'' teriaknya pada
Shizuka, tapi si penyerang yang terluka itu
keburu kabur ke arah kerumunan. Para
penjaga berhasil menangkapnya tapi tidak
berhasil menyelamatkannya dari kemarahan
kerumunan.
Shigeko tidak terlalu kaget dengan
serangan itu tapi lebih merasa heran dengan
serangan yang ceroboh juga gagal itu. Ia
mengira para pembunuh bayaran akan lebih
mematikan, tapi ketika penjaga datang
menghampiri ke pelataran untuk mengikat
dua penyerang yang masih hidup dengan tali
kemudian menggiring mereka pergi, tampak
olehnya wajah mereka di bawah cahaya
lentera.
"Mereka masih muda! Tak jauh lebih tua
dari usiaku!"
Tatapan gadis itu beradu pandang dengan-
nya. Tidak akan dilupakannya tatapan penuh
kebencian itu. Itulah pertama kalinya
Shigeko tersadar betapa ia sudah hampir
melakukan pembunuhan, dan sekaligus lega
dan bersyukur karena tidak mencabut nyawa
kedua orang yang masih muda ini, yang
nyaris sebaya dengan dirinya.*
"Mereka putra-putrinya Gosaburo," kata
Takeo tak Lima setelah memerhatikan
mereka. Terakhir aku lihat mereka di
Matsue, mereka masih bayi." Nama mereka
tertulis dalam silsilah keluarga Kikuta, di-
tambahkan ke catatan Tribe yang dikumpul-
kan Shigeru. Si pemuda, putra kedua
Gosaburo bernama Yuzu, sedangkan yang
perempuan bernama Ume. Dan yang tewas
bernama Kunio, anak sulung, salah satu anak
laki-laki yang pernah menjalani pelatihan
bersama Takeo.
Saat itu merupakan hari pertama di tahun
baru. Para tawanan dibawa menghadap
Takeo di dalam salah satu ruang tahanan di
lantai paling bawah kastil Inuyama. Mereka
berlutut di hadapannya, dengan wajah pucat
tapi tanpa ekspresi. Tangan mereka diikat
kencang ke belakang, tapi bisa dia lihat kalau
pun lapar atau haus, tapi mereka tidak
diperlakukan dengan kasar. Sekarang ia harus
memutuskan apa yang harus dilakukan
dengan mereka.
Kemarahan sebelumnya atas serangan
terhadap keluarganya diredakan oleh harapan
bahwa kemungkinan situasi bisa berbalik
menguntungkan baginya: kegagalan terbaru
ini, setelah kegagalan-kegagalan yang se-
belumnya, mungkin akhirnya bisa mem-
bujuk keluarga Kikuta untuk menyerah,
untuk bisa berdamai.
Aku sudah terlalu berpuas diri, pikirnya.
Aku yakin kalau aku kebal terhadap serangan
mereka: aku tidak memperhitungkan mereka
akan menyerang keluargaku.
Ketakutan baru menyelimutinya saat
teringat kata-katanya pada Kaede pada hari
sebelumnya. Ia tak mampu mcmbayangkan
bisa bertahan hidup jika istrinya tiada,
kehilangannya; begitu pula dengan negara-
nya.
"Apakah mereka mengatakan sesuatu
padamu?" tanyanya pada Muto Taku yang
kini berusia dua puluh enam tahun, anak
bungsu Muto Shizuka. Ayahnya dulu meru-
pakan bangsawan besar, sekutu dan saingan
Takeo, Arai Daiichi. Kakak Taku, Zenko,
mewarisi wilayah kekuasaan ayahnya di
Barat, dan Takeo ingin memberi Taku
warisan dengan cara yang sama; tapi
ditolaknya, seraya mengatakan bahwa dia tak
ingin memiliki wilayah kekuasaan dan
kehormatan. Dia lebih memilih bekerja
dengan paman dari ibunya. Kenji, dalam
mengendalikan jaringan mata-mata yang
telah Takeo bangun melalui Tribe. Dia
menerima pernikahan politis dengan gadis
Tohan yang disukainya dan telah memberi-
nya seorang putra dan seorang putri. Orang
cenderung meremehkannya, yang justru
disukainya. Sosok dan wajah Taku menurun
dari keluarga Muto sedangkan Arai mewarisi
keberanian dan kegagahannya, serta pada
dasarnya menganggap hidup itu menyenang-
kan dan pengalaman yang mengasyikkan.
Taku tersenyum saat menjawab. "Tidak.
Mereka menolak bicara. Aku hanya terkejut
mereka masih hidup; kau tahu kalau Kikuta
bunuh diri dengan menggigit lidah mereka
sendiri! Tentu saja, aku belum berusaha
sebegitu kerasnya untuk membujuk mereka."
"Aku tidak harus mengingatkanmu kalau
kekerasan dilarang di Tiga Negara."
"Tentu saja tidak. Tapi apakah peraturan
itu juga berlaku bahkan untuk Kikuta?"
"Peraturan itu berlaku bagi semua orang,"
sahut Takeo ringan. "Mereka bersalah atas
percobaan pembunuhan dan akan dieksekusi
atas kesalahan itu pada akhirnya nanti.
Untuk saat ini mereka tidak boleh diperlaku-
kan dengan kasar. Akan kita lihat seberapa
kuat keinginan ayah mereka agar anak-
anaknya bisa kembali."
"Mereka berasal dari mana?" selidik
Sonoda Mitsuru, yang menikah dengan adik
Kaede, Ai, dan meskipun keluarganya, Akita,
dulunya adalah pengawal Arai, ia diyakinkan
untuk bersumpah setia pada Otori dalam
perdamaian besar-besaran setelah gempa.
Sebagai imbalannya, dia dan Ai diberikan
wilayah Inuyama. "Di mana bisa kau
menemukan Si Gosaburo ini?"
"Kukira di pegunungan di luar perbatasan
wilayah timur," tutur Taku, dan Takeo
melihat si gadis sedikit memicingkan mata.
Sonoda berkata, "Maka untuk sementara
waktu tidak mungkin mengadakan
perundingan, karena salju pertama akan
turun dalam minggu ini."
"Musim semi nanti kita akan kirim surat
pada ayah mereka," sahut Takeo. "Tidak ada
salahnya membuat batin Gosaburo men-
derita memikirkan nasib anaknya. Bahkan
mungkin membuatnya semakin ingin
menyelamatkan mereka. Sementara itu, tetap
rahasiakan identitas mereka dan jangan
biarkan mereka berhubungan dengan orang
lain selain kau."
Didekatinya Taku. "Pamanmu berada di
kota, kan?"
"Ya; paman akan bergabung dengan kita
di kuil untuk perayaan Tahun Baru, tapi
kesehatannya sedang tidak baik, dan udara
malam yang dingin menimbulkan kejang
otot yang membuatnya batuk-batuk."
"Besok aku akan memanggilnya. Apakah
dia berada di rumah lama?"
Taku mengangguk. "Paman menyukai
aroma pabrik pembuatan sake. Menurutnya
udara di sana lebih mudah dihirup."
"Kurasa sakenya juga ikut membantu."
***
"Hanya ini kesenangan yang tersisa untuk-
ku," ujar Muto Kenji, seraya mengisi cangkir
Takeo dan memberikan botol sake kepada-
nya. "Ishida memintaku mengurangi minum,
mengatakan kalau alkohol buruk bagi paru-
paru, tapi... sake membuatku tetap ber-
semangat dan membantuku agar bisa tidur."
Takeo menuang sake yang bening serta
keras ke cangkir gurunya yang sudah tua itu.
"Ishida juga memintaku mengurangi minum
sake," akunya saat mereka berdua menenggak
habis minumannya. "Tapi bagiku sake
meredakan rasa sakitku. Dan Ishida pun
hampir tidak mengikuti sarannya sendiri, lalu
mengapa kita harus mengikuti anjurannya?"
"Kita adalah dua orang laki-laki tua,"
sahut Kenji, tertawa. "Siapa yang bisa
mengira, melihatmu mencoba membunuhku
tujuh belas tahun yang lalu di rumah ini,
kalau kita akan duduk di sini saling mem-
bandingkan penyakit?"
"Bersyukurlah kita berdua masih hidup
sampai saat ini!" timpal Takeo. Ia melihat ke
sekeliling rumah yang dibangun begitu kuat
dengan langit-langit tinggi, pilar kayu cedar
dan beranda serta penutup jendela dari kayu
cemara cypress. Rumah ini penuh kenangan.
"Ruangan ini amat jauh lebih nyaman
ketimbang lemari terkutuk tempat aku
dikurung!"
Kenji tertawa lagi. "Itu hanya karena kau
bertingkah bak hewan liar! Keluarga Muto
selalu menyukai kemewahan. Dan kini
bertahun-tahun dalam kedamaian, per-
mintaan akan produk buatan kami membuat
kami sangat kaya raya, berkat kau, Lord
Otoriku tercinta." Dinaikkan cangkirnya ke
arah Takeo; mereka berdua minum lagi,
kemudian mengisi lagi wadah mereka
masing-masing.
"Rasanya aku akan menyesal meninggal-
kan semua ini, Aku sangsi masih bisa
menyaksikan Tahun Baru." kata Kenji. Tapi
kaukau tahu orang bilang kalau kau tak
bisa mati!"
Takeo tertawa. "Tidak ada manusia yang
tidak bisa mati. Kematian menantiku sama
halnya seperti semua orang. Hanya saja
waktuku belum tiba."
Kenji adalah salah satu dari sedikit orang
yang tahu isi ramalan tentang Takeo, ter-
masuk bagian yang dirahasiakannya: bahwa
ia aman dari kematian kecuali di tangan
putranya sendiri. Semua sisa ramalannya
telah menjadi kenyataan, sampai tahap ini:
lima pertempuran telah membawa kedamai-
an di Tiga Negara, dan Takeo berkuasa dari
ujung laut ke ujung laut lainnya. Gempa
bumi yang menyengsarakan mengakhiri
pertempuran terakhir serta menyapu habis
pasukan Arai Daiichi, bisa digambarkan
sebagai memenuhi keinginan Surga. Dan
sejauh ini, tak seorang pun bisa membunuh
Takeo, membuat ramalan yang terakhir ini
semakin bisa di percaya.
Takeo berbagi banyak rahasia dengan
Kenji, yang dulu pernah menjadi gurunya di
Hagi. Dengan bantuan Kenji, Takeo berhasil
menembus kastil di Hagi dan membalaskan
dendam atas kematian Shigeru. Kenji orang
yang pintar, cerdik tanpa perasaan senti-
mentil. Kenji adalah utusan dan juru runding
yang baik, dan membuat Takeo sangat
mengandalkannya. Kenji tidak punya hasrat
lain di luar kegemarannya yang abadi pada
sake dan perempuan dari rumah bordil
setempat. Tampak tidak peduli pada harta
benda, kekayaan maupun status. Mengabdi-
kan hidupnya pada Takeo dan bersumpah
untuk melayaninya; memiliki kasih sayang
istimewa atas Lady Otori, yang dikaguminya;
amat menyayangi keponakannya sendiri,
Shizuka; dan rasa hormat pada putra
Shizuka, Taku, ahli mata-mata; namun sejak
kematian putrinya, Kenji semakin terasing-
kan dari istrinya, Seiko, yang meninggal
beberapa tahun lalu, dan tak memiliki baik
ikatan cinta maupun kebencian dengan
orang lain.
Semenjak kematian Arai dan para lord
Otori enam belas tahun yang lalu, Kenji
bekerja dengan kesabaran dan cerdik
terhadap tujuan Takeo: menarik semua
sumber daya dan perangkat kekerasan ke
tangan pemerintahan, mengendalikan
kekuatan prajurit perseorangan dan
kelompok bandit yang tak mengenal hukum.
Kenjilah yang tahu keberadaan kelompok
rahasia masyarakat kuno yang tidak diketahui
TakeoKesetiaan pada Burung Bangau,
Amarah Macan Putih, Jalan Sempit Ular
petani dan penduduk desa menggabungkan
diri dalam kelompok masyarakat ini selama
masa-masa anarkis. Kelompok ini kini
dimanfaatkan dan terus dibangun agar
masyarakatnya bisa mengatur masalah
mereka sendiri di tingkat desa dan memilih
sendiri pemimpinnya untuk mewakili mereka
dan mengajukan tuntutan atas ketidakpuasan
atau keluhan mereka di pengadilan tingkat
propinsi.
Pengadilan diatur oleh klas ksatria; anak
laki-laki mereka dengan pola pikir yang tidak
terlalu militer, dan terkadang juga anak
perempuan, dikirim ke sekolah-sekolah besar
di Hagi, Yamagata dan Inuyama untuk
mempelajari etika pelayanan, pembukuan
dan ekonomi, sejarah serta bahasa dan
kesusastraan klasik. Saat kembali ke daerah
asal, mereka memegang jabatan tertentu,
diberi status dan penghasilan yang cukup:
mereka bertanggung jawab langsung kepada
tetua dari setiap klan, tanggung jawab yang
sama juga dipikul pemimpin klan; para
pemimpin klan ini bertemu Takeo dan
Kaede secara teratur untuk membahas soal
kebijakan, menentukan besarnya pajak serta
mempertahankan pelatihan dan
perlengkapan pasukan. Setiap daerah harus
menyediakan sejumlah orang icrbaik untuk
pasukan pusat: separuh tentara, dan sepa-ruh
lagi petugas keamanan yang bertugas
menangani bandit dan penjahat lainnya.
Kenji menangani semua administrasi
dengan trampil, mengatakan kalau cara ini
mirip hirarki Tribehanya saja ada per-
bedaan yang mendasar: kekerasan dilarang,
dan membunuh serta menerima suap di-
ancam hukuman mati. Aturan yang terakhir
terbukti paling sulit dilaksanakan. Tribe
mendapat cara untuk menghindar, tapi
mereka tidak bertransaksi dalam jumlah besar
atau memamerkan kekayaan. Makin kuatnya
usaha Takeo membasmi korupsi membawa
hasil, korupsi dan suap makin berkurang.
Lalu bentuk praktik yang lain berjalan:
praktik tukar menukar hadiah dalam bentuk
keindahan dan selera, di mana nilainya
tersembunyi. Hal ini menyebabkan datang-
nya para perajin dan seniman ke Tiga
Negara, bukan hanya mereka yang berasal
dari Delapan Pulau tapi juga dari negeri-
negeri di daratan utama, Silla, Shin dan
Tenjiku.
Setelah gempa mengakhiri perang di Tiga
Negara, para ketua dari keluarga dan klan
yang masih hidup bertemu di Inuyama dan
menerima Otori Takeo sebagai pemimpin
mereka. Semua pertikaian karena hubungan
darah yang menentang Takeo maupun per-
cekcokan antara mereka sendiri dinyatakan
berakhir. Terjadi pemandangan yang meng-
harukan saat para ksatria saling berdamai
setelah puluhan tahun bermusuhan. Namun
Takeo dan Kenji menyadari bahwa ksatria
terlahir untuk bertarung: masalahnya,
mereka akan bertarung melawan siapa? Dan
jika mereka tidak bertarung, bagaimana
menyibukkan mereka?
Beberapa prajurit menjaga perbatasan di
wilayah Timur, tapi hanya terjadi sedikit
peristiwa dan musuh utama mereka adalah
rasa jenuh; beberapa yang lainnya men-
dampingi Terada Fumio dan tabib Ishida
dalam perjalanan penjelajahan mereka,
melindungi kapal dagang di laut dan toko
serta gudang mereka di pelabuhan yang jauh;
yang lainnya mengikuti lomba yang dibuat
Takeo untuk keahlian berpedang dan
memanah; sedang yang lainnya dipilih untuk
mengikuti jalan utama dari pertarungan:
penguasaan diri, Ajaran Houou.
Ajaran Houou bermarkas di Biara
Terayama yang dipimpin kepala biara
Matsuda Shingen dan Kubo Makoto. Ajaran
ini hanya dapat diikuti segelintir laki-laki
dan perempuandengan kekuatan fisik dan
mental yang hebat. Keahlian Tribe adalah
bakat dari lahirpendengaran dan peng-
lihatan yang sangat kuat, kemampuan
menghilang, penggunaan sosok keduatapi
sebagian besar manusia memiliki kemampu-
an seperti ini namun belum terasah.
Menemukan dan memurnikan kemampuan
seperti inilah yang menjadi inti Ajaran
Houou, mengambil nama burung suci yang
bersarang jauh di dalam hutan-hutan di
sekitar Terayama.
Sumpah pertama yang dilakukan para
ksatria yang terpilih ini yaitu tidak mem-
bunuh, baik nyamuk atau pun manusia,
bahkan demi membela diri. Kenji meng-
anggap itu aturan yang gila karena dia sering
menikam jantung orang, membunuh dengan
garotte, menyisipkan racun ke dalam cangkir,
mangkuk atau bahkan langsung ke orang
yang tidur dengan mulut menganga. Berapa
banyak? Dia tak bisa menghitungnya lagi.
Tak ada penyesalan atas mereka yang telah
dikirimnya ke alam bakacepat atau lambat
manusia juga akan mati. Dia melihat bahwa
larangan membunuh ternyata jauh lebih
berat daripada keputusan untuk membunuh.
Dia tak kebal dengan kedamaian dan
kekuatan spiritual Terayama. Akhir-akhir ini
kesenangan terbesarnya yaitu menemani
Takeo di sana dan menghabiskan waktu
bersama Matsuda dan Makoto.
Disadarinya kalau akhir hidupnya sudah
dekat. Ia sudah tua; kesehatan dan kekuatan-
nya makin memburuk: selama berbulan-
bulan paru-parunya terasa makin lemah dan
seringkali muntah darah.
Takeo berhasil menjinakkan baik Tribe
maupun para ksatria: hanya Kikuta yang
masih bertahan menentangnya. Kikuta
bukan hanya berusaha membunuhnya tapi
juga bersekutu dengan ksatria yang kurang
puas, melakukan pembunuhan secara acak
dengan harapan menggoyahkan kestabilan
masyarakat, menyebarkan desas-desus.
Takeo angkat bicara lagi, lebih serius.
"Serangan yang terakhir ini membuatku jauh
lebih waspada karena ditujukan pada
keluargaku, bukan diriku. Jika istri atau
anakku mati, itu akan menghancurkan
diriku, dan Tiga Negara."
"Kurasa itulah tujuan Kikuta," sahut Kenji
ringan.
"Kapan mereka akan berhenri?"
"Akio takkan berhenri. Kebenciannya
padamu hanya akan berakhir dengan
kematiannyaatau kematianmu. Dia telah
mengabdikan hidupnya demi tujuannya itu."
Wajah Kenji berubah tenang dan bibimya
berkerut menggambarkan kegetiran. Ia
minum lagi. "Tapi Gosaburo seorang
pedagang dan pragmatis: dia akan ketakuian
setengah mati bila kehilangan anak-
anaknyasatu putranya telah tewas, dan
nasib dua lainnya ada di tanganmu.
Mungkin kita bisa memberinya sedikit
tekanan."
"Kupikir juga begitu. Kita akan biarkan
dua anaknya yang tersisa tetap hidup hingga
musim semi, kemudian melihat apakah ayah
mereka siap untuk berunding."
"Mungkin sementara ini kita juga bisa
mengorek keterangan yang berguna dari
keduanya," gerutu Kenji.
Takeo menaikkan pandangannya ke arah
Kenji melalui pinggiran cangkir.
"Baiklah, baiklah, lupakan saja aku pernah
mengatakannya," gerutu laki-laki tua itu.
"Tapi kau bodoh bila tidak menggunakan
cara sama seperti yang digunakan musuh-
musuhmu." Digelengkan kepalanya. "Aku
berani bertaruh kalau kau masih juga
menyelamatkan laron dari lilin. Kelembutan
itu tidak pernah hilang."
Takeo tersenyum tipis tapi tidak mem-
bantahnya. Sulit rasanya untuk keluar dari
apa yang pernah diajarkan padanya sewaktu
ia masih kecil. Hasil didikan di antara kaum
Hidden telah membuatnya teramat sangat
enggan untuk mencabut nyawa manusia.
Namun sejak berusia enam belas tahun nasib
membimbingnya ke jalan hidup ksatria:
menjadi pewaris sebuah klan besar dan
sekarang menjadi pemimpin Tiga Negara; ia
harus belajar menjalani hidup dengan ajaran
pedang. Lebih jauh lagi, Tribe, Kenji sendiri,
mengajarkan padanya berbagai cara untuk
membunuh dan pernah berusaha memadam-
kan sifat welas asih dalam dirinya. Dalam
perjuangannya membalaskan dendam
Shigeru dan menyatukan Tiga Negara dalam
kedamaian, ia melakukan begitu banyak
tindak kekerasan, banyak di antaranya amat
disesalinya, sebelum belajar cara
menyeimbangkan antara kekerasan dan welas
asih, sebelum kemakmuran dan stabilitas
negara serta peraturan hukum memberikan
pilihan dengan cara yang diinginkan pada
konflik kekuasaan yang buta antar klan.
"Aku ingin bertemu dengan bocah itu
lagi," ujar Kenji tiba-iiba. "Mungkin ini akan
menjadi kesempatan terakhir bagiku."
Ditatapnya Takeo lekat-lekat. "Kau telah
memutuskan apa yang harus kita lakukan
padanya?"
Takeo menggeleng. "Aku tidak bisa meng-
ambil keputusan. Apa yang bisa kulakukan?
Kemungkinan besar keluarga Mutokau
menginginkannya kembali, kan?"
"Tentu. Tapi Akio mengatakan pada istri-
ku, yang berhasil menghubunginya sebelum
mati, bahwa lebih baik dia yang bunuh anak
itu ketimbang menyerahkannya, baik ke
tangan Muto atau ke tanganmu."
"Bocah yang malang. Didikan apa yang
didapatkannya!" seru Takeo.
"Ya, Tribe membesarkan anak-anak
mereka dengan didikan yang sangat keras,"
sahut Kenji.
"Apakah dia tahu kalau aku ayahnya?"
"Itu salah satu hal yang bisa kucari tahu."
"Kau kurang sehat untuk misi semacam
ini," kata Takeo dengan nada enggan, karena
ia tak bisa memikirkan ada orang lain yang
bisa melakukannya.
Kenji menyeringai. "Kesehatanku yang
buruk justru menjadi alasan mengapa aku
harus pergi. Bila aku tidak sempat melihat
tahun ini berakhir, maka sekalian saja kau
manfaatkan diriku ini! Lagipula, aku ingin
bertemu dengan cucuku sebelum aku mati.
Aku akan berangkat saat salju mulai men-
cair."
Sake, penyesalan dan kenangan meluapkan
perasaan haru Takeo. Ia berdiri lalu me-
rangkul gurunya yang sudah tua itu.
"Sudah, sudah!" ujar Kenji, menepuk-
nepuk bahunya. "Kau tahu betapa bencinya
aku bila menunjukkan perasaan seperti ini.
Sering-seringlah datang dan temui aku
sepanjang musim dingin ini. Kita akan masih
punya kesempatan untuk adu minum sake
bersama."*
Anak laki-laki itu, Hisao, kini telah berusia
enam belas tahun. Wajahnya tidak mirip
orang yang dipercaya sebagai ayahnya,
Kikuta Akio, maupun ayah kandungnya yang
belum pernah dilihatnya. Tidak mewarisi ciri
fisik Muto, keluarga ibunya, maupun
keluarga Kikutadan kian lama kian jelas
terlihat kalau dia tak mewarisi kemampuan
magis Tribe. Pendengarannya tak lebih peka
dibandingkan anak seusianya; dia pun tak
memiliki kemampuan menghilang. Pelatihan
sejak kecil membuat fisiknya kuat dan gesit,
namun tak bisa melompat atau pun terbang
seperti ayahnya. Satu-satunya cara yang bisa
dilakukannya agar orang tertidur yaitu rasa
bosan karena dia jarang bicara. Andai dia
buka mulut, bicaranya pelan, tersendat-
sendat, tanpa ada tanda-tanda kecerdasan
atau kreativitas.
Akio adalah Ketua Kikuta, keluarga ter-
besar dalam Tribe, yang menguasai berbagai
kemampuan serta bakat yang kini mulai
lenyap. Sejak kecil Hisao sudah menyadari
kekecewaan ayahnya pada dirinya.
Karena Tribe membesarkan anak mereka
dengan cara sangat keras, melatih mereka
dengan kepatuhan mutlak, bertahan me-
nahan lapar, haus, panas, dingin dan rasa
sakit yang luar biasa, serta melenyapkan
semua perasaan, simpati maupun welas asih.
Akio sangat keras pada putra tunggalnya itu
dan tak pernah menunjukkan pengertian
maupun kasih sayang. Perlakuan Akio yang
kejam, bahkan mengejutkan kerabatnya
sendiri. Tapi Akio adalah Ketua keluarga,
penerus pamannya, Kotaro, yang mati di
Hagi oleh Otori Takeo dan Muto Kenji.
Dan sebagai Pimpinan, Akio bisa bertindak
sesuka hati; tak seorang pun bisa meng-
kritiknya.
Akio tumbuh menjadi laki-laki sinis dan
susah ditebak. Dia selalu menyalahkan Otori
Takeo atas terpecah-belahnya Tribe,
kematian Kotaro yang disayangi, serta
kematian pesumo tangguh, Hajime, serta
banyak kematian lainnya. Keluarga Kikuta
dikejar-kejar sehingga mereka keluar dari
Tiga Negara untuk pindah ke Utara,
meninggalkan usaha mereka yang meng-
hasilkan banyak uang.
Anak-anak Kikuta tidur dengan kaki
mengarah ke Barat, dan saling menyapa
dengan kalimat, "Apakah Otori sudah mati?"
dan dibalas dengan, "Belum, tapi tak lama
lagi."
Konon kabarnya kematian istrinya, Muto
Yuki, dan kematian Kotaro yang membuat
Akio begitu penuh dendam dan hidup dalam
kebencian. Para tetua mengatakan kalau Yuki
meninggal karena demam setelah melahir-
kan, tapi tampaknya Hisao sudah tahu yang
sebenarnya: ibunya mati diracun. Dapat
dilihatnya kejadian itu dengan jelas, seolah
menyaksikan dengan mata bayinya yang
masih belum fokus. Keputusasaan dan
kemarahan ibunya, kesedihan karena harus
meninggalkan putranya; penolakan ibunya
saat dipaksa menelan pil racun; jerit dan
tangis ibunya; seringai puas Akio karena
sebagian dendamnya terlaksana; penderitaan
dan kenikmatan keji yang dirasakan Akio
menjadi awal mula tenggelamnya dia dalam
kekejaman.
Hisao merasakan ini seiring ia tumbuh
dewasa; tapi lupa bagaimana ia tahu itu.
Apakah ia memimpikannya, atau ada yang
menceritakannya? Ia ingat ibunya lebih jelas
dari yang seharusnyausianya baru beberapa
hari saat ibunya meninggaldan menyadari
adanya hubungan dirinya dengan sang ibu.
Seringkali ia merasakan kalau ibunya meng-
inginkan sesuatu darinya, tapi ia takut men-
dengarkan karena itu berarti ia membuka diri
memasuki alam baka. Antara kemarahan si
hantu dan rasa enggan dalam dirinya, kepala-
nya terasa seperti terbelah karena rasa sakit.
Itu sebabnya dia mengetahui kemarahan
ibunya dan sakit hati ayahnya, dan itu
membuat ia benci sekaligus iba pada Akio.
Hal-hal buruk yang terjadi di antara mereka
berdua yang setengah menakutkan, setengah
diharapkan, karena hanya saat itulah ada
orang yang memeluknya atau kelihaian
membutuhkan dirinya.
Hisao tidak pernah menceritakannya
sehingga tak seorang pun tahu satu bakat
Tribe yang telah hilang selama beberapa
generasi ternyata ada pada dirinya.
Kemampuan mengarungi dua dunia, men-
jadi penghubung antara arwah dengan orang
yang masih hidup. Anugerah semacam ini
semestinya diasah dan pemiliknya akan
ditakuti serta dihormati; tapi Hisao tak tahu
cara mengatur bakatnya ini; apa yang
dilihatnya di alam baka tampak berkabut dan
sulit dimengerti: ia tidak mengetahui simbol
dan bahasa untuk berkomunikasi dengan
arwah.
Ia hanya tahu kalau hantu itu adalah
ibunya yang mati dibunuh.
Meskipun Hisao suka membuat kerajinan
tangan, dan menyukai hewan, namun ia
merahasiakannya. Sekali dia terlihat meng-
elus seekor kucing, yang kemudian ia lihat
hewan malang itu digorok ayahnya di
hadapannya. Roh kucing itu juga sesekali
seperti menjerat Hisao dari dunianya, dan
lolongan yang memusingkan terdengar
makin keras hingga ia tak percaya kalau
orang lain tak mendengarnya. Ketika alam
baka membuka jalan dan mengajaknya
masuk, kepalanya luar biasa sakit, dan satu
sisi matanya menjadi gelap. Satu-satunya cara
meredakan rasa sakit dan suara-suara si
kucing serta si hantu perempuan adalah
membuat benda-benda dengan tangannya. Ia
membangun kincir air dan orang-orangan
dari bambu untuk menakuti rusa, seolah
pengetahuan itu sudah ada dalam darahnya.
Ia dapat membuat ukiran kayu berbentuk
hewan yang begitu hidup hingga tampak
seperti hewan yang disihir menjadi patung. Ia
menyukai semua aspek penempaan: mem-
buat besi dan baja, pedang, pisau serta ber-
bagai peralatan.
Keluarga Kikuta ahli membuat senjata,
terutama sen-jata rahasia Tribepisau
lempar, jarum, belati kecil dan sebagainya
tapi mereka tak tahu cara membuat senjata
yang disebut senjata api. Senjata yang
digunakan Otori begitu dirahasiakan cara
buatnya hingga membuat orang iri. Keluarga
Kikuta terpecah untuk memiliki senjata itu.
Ada yang beranggapan senjata itu meng-
hilangkan semua kemampuan dan ke-
nikmatan dalam membunuh, kalau cara
tradisional lebih bisa diandalkan; sementara
yang lainnya beranggapan kalau ingin
menyingkirkan Otori, mereka harus me-
nyeimbangkan kekuatan dengan memiliki
senjata yang sama.
Namun usaha mereka untuk mendapatkan
senjata api selalu gagal. Otori membatasi
penggunaan senjata ini hanya untuk se-
kelompok kecil orang: setiap pucuk senjata
api yang ada di negara ini dihitung. Jika ada
yang hilang, si pemilik harus membayar
dengan nyawanya. Senjata ini pernah sekali
digunakan orang barbar. Sejak itu semua
orang barbar digeledah ketika datang,
senjata-senjata mereka dirampas dan mereka
hanya boleh berdagang di pelabuhan Hofu.
Tapi berbagai laporan tentang pembunuhan
yang memakan banyak korban jiwa terbukti
sama efektifnya dengan senjata itu sendiri:
semua musuh Otori, termasuk Kikuta,
berusaha mendapatkan senjata itu dengan
cara mencuri, berkhianat, atau mencari
sendiri.
Senjata-senjata milik Otori bentuknya
panjang, berat serta tidak praktis: kurang
prakris menurut cara pembunuhan yang
dibanggakan Kikuta. Senjata-senjata itu tak
bisa disembunyikan dan digunakan dengan
cepat; bila terkena air maka senjata itu tak
berguna. Hisao mendengar ayahnya dan
seorang laki-laki yang lebih tua membahas
benda ini, dan ia membayangkan senjata api
yang kecil dan ringan, yang bisa di-
sembunyikan di balik pakaian dan tak ber-
suara, senjata yang bahkan tak mampu di-
lawan Otori Takeo.
Setiap tahun ada saja pemuda yang ingin
menjadi pahlawan, atau orang tua yang ingin
mati terhormat yang pergi hendak mem-
bunuh Otori Takeo untuk membalaskan
kematian Kikuta Kotaro dan anggota Tribe
lainnya. Mereka tak pernah kembali: kabar
tentang tertangkapnya mereka datang
beberapa bulan kemudian. Mereka disidang
di depan umum yang disebut sebagai
pengadilan Otori, dan dieksekusi.
Ada kalanya Otori Takeo dilaporkan ter-
luka sehingga harapan mereka membumbung
tinggi, tapi dia selalu sembuh, bahkan dari
racun, seperti pulihnya dia dari belati
beracun milik Kotaro. Mendengar desas-
desus kalau Otori tak bisa mati membuat
kebencian serta kegeriran Akio semakin ber-
tambah. Akio mulai bersekutu dengan
musuh Takeo lainnya, menyerangnya melalui
istri atau anak-anaknya. Tapi cara ini juga
terbukti gagal. Keluarga Muto yang sudah
bersumpah setia pada Otori telah meng-
gandeng keluarga Tribe lainnya: Imai,
Kuroda dan Kudo. Sejak keluarga Tribe
melakukan perkawinan campuran, banyak
pengkhianat yang memiliki darah Kikuta, di
antaranya adalah Muto Shizuka serta kedua
putranya, Taku dan Zenko. Taku seperti ibu
dan paman buyutnya, mempunyai banyak
kemampuan, memimpin jaringan mata-mata
dan melindungi Otori; sementara Zenko,
yang kurang berbakat, bersekutu dengan
Otori melalui pernikahan: mereka bersaudara
ipar.
Belakangan sepupu Akio, dua putra
Gosaburo, diutus bersama saudari
perempuan mereka ke Inuyama tempat
keluarga Otori merayakan Tahun Baru.
Mereka berbaur dalam kerumunan di biara
dan mencoba menikam Lady Otori dan
putri-putrinya. Apa yang terjadi setelah itu
tidak jelas, lapi ternyata para perempuan
yang menjadi sasaran berhasil mempertahan-
kan diri dengan kekejaman yang tak terduga:
salah satu penyerang, putra sulung Gosaburo,
terluka dan dipukuli sampai mati oleh
kerumunan orang. Sedang yang lainnya
berhasil ditangkap dan dibawa ke kastil
Inuyama. Tak ada yang tahu apakah mereka
masih hidup atau sudah mati.
Kehilangan tiga anggota muda yang ada
hubungan erat dengan sang Ketua merupa-
kan pukulan berat. Karena hingga musim
semi tiba masih belum ada kabar tentang
kedua orang yang ditawan, Kikuta menduga
mereka sudah mati. Ritual pemakaman mulai
diatur dalam kedukaan yang mendalam
karena tak ada jenazah yang bisa dibakar dan
tak ada abu jenazah.
Suatu sore Hisao bekerja seorang diri di
sepetak kecil sawah, jauh di kedalaman
pegunungan. Selama malam-malam di
musim dingin yang panjang, ia telah me-
mikirkan cara mengaliri sawah dengan me-
manfaatkan kincir air. Ia menghabiskan
musim dingin membuat ember dan tali:
embernya dibuat dari bambu yang paling
ringan dan talinya diperkuat dengan batang
tanaman rambat yang cukup kaku untuk bisa
mengangkat ember kincir.
Hisao tengah berkonsentrasi penuh pada
pekerjaannya, tiba-tiba katak terdiam. Ia
tengok kanan-kiri. Tak ada orang, tapi ia
tahu ada orang yang menggunakan
kemampuan menghilang Tribe.
Mengira itu hanya salah satu anak yang
datang membawa pesan, dia berseru, "Siapa
di sana?"
Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan
usia tak bisa diperkirakan dan berpenampilan
biasa berdiri di hadapannya. Tangan Hisao
segera bergerak ke arah pisaunya karena
yakin ia belum mengenal orang itu. Sosok
laki-laki itu bergoyang-goyang selagi meng-
hilang. Hisao merasakan jari-jari yang tak
terlihat memiting pergelangan tangannya dan
ototnya langsung terasa lumpuh saat telapak
tangannya terbuka dan pisaunya terjatuh.
"Aku takkan menyakitimu," ujar orang
itu, dan menyebut namanya dengan cara
yang membuat Hisao percaya padanya, dan
dunia ibunya menyelubungi ambang batas
dunianya; dirasakan kebahagiaan dan
pendcritaan ibunya dan pertanda pertama
dari sakit kepalanya serta kemampuan
melihat separuh dari dua dunia yang ber-
beda.
"Siapa kau?" bisiknya, segera menyadari
kalau orang mi dikenal ibunya.
"Kau bisa melihatku?" sahut laki-laki itu.
"Tidak. Aku tak memiliki kemampuan
menghilang, maupun mengenalinya."
"Tapi tadi kau mendengarku mendekat,
kan?"
"Hanya dari katak. Aku mendengarkan
mereka. Tapi aku tak bisa mendengar dari
jauh. Aku tidak tahu orang yang bisa
melakukannya di kalangan Kikuta saat ini."
Ia heran telah bersikap biasa dan bebas
pada orang yang belum dikenalnya.
Orang itu kembali menampakkan diri
dalam jarak serentangan tangan dari wajah
Hisao. Sorot matanya tajam dan kelihatan
penuh selidik.
"Kau tidak memiliki satu pun kemampuan
Tribe?" tuturnya.
Hisao mengangguk, kemudian mengalih-
kan pandangannya ke seberang lembah.
"Kau bcrnama Kikuta Hisao, putra Akio?"
"Ya, dan ibuku bemama Muto Yuki."
Ekspresi wajah orang itu agak berubah,
dan dirasakan reaksi penyesalan serta rasa iba
ibunya.
"Sudah kuduga. Kalau begitu, aku kakek-
mu: Muto Kenji."
Hisao menyerap semua keterangan ini.
Sakit kepalanya kian menjadi-jadi: Muto
Kenji adalah pengkhianat, kebencian Kikuta
pada orang ini hampir sama besarnya seperti
kebencian pada Otori Takeo, namun
kehadiran ibunya terasa membebani dirinya
dan bisa dirasakan ibunya memanggil,
"Ayah!"
"Apa itu?" tanya Kenji.
"Bukan apa apa. Kadang-kadang kepalaku
sakit. Aku sudah biasa. Mengapa kau kemari?
Kau akan dibunuh. Seharusnya aku mem-
bunuhmu, tapi kau bilang kalau kau kakek-
ku, lagipula aku tidak ahli membunuh."
Pandangannya turun menatap ke konstruksi
yang tengah dikerjakannya. "Aku lebih suka
membuat benda-benda."
Betapa anehnya, pikir orang tua itu. Dia
tidak punya kemampuan apa pun, baik dari
ayah maupun dan ibunya. Rasa kecewa dan
lega menyapu dirinya. Mirip siapa dia? Tidak
mirip Kikuta, Muto, maupun Otori. Dia pasti
mirip ibunya Takeo, berkulit gelap dan
berwajah lebar.
Kenji menatap bocah di hadapannya
dengan tatapan iba, tahu betapa kerasnya
masa kanak-kanak di Tribe, apalagi pada
mereka yang tak berbakat. Jelas sekali Hisao
punya beberapa kemampuan: benda itu
dibuat dengan kreatif dan dengan keahlian
tinggi. Dan ada sesuatu yang lain pada
dirinya, gerakan matanya yang cepat menun-
jukkan kalau dia bisa melihat hal lain. Apa
yang bisa dilihatnya? Pemuda ini berbadan
sehat, agak lebih pendek dari Kenji sendin
tapi kuat, dengan kulit mulus tanpa cacat
dan rambut tebal serta mengkilap, mirip
rambut Takeo.
"Mari kita temui Akio," ajak Kenji. "Ada
yang aku sampaikan padanya."
Ia tidak bersusah payah menyembunyikan
sosoknya selagi mengikuti bocah itu
menuruni jalan setapak dari atas gunung
menuju desa. Sadar kalau akhirnya ia akan
dikenali jugasiapa lagi yang bisa sampai
sejauh ini, menghindari para penjaga di
gerbang, bergerak tak terlihat dan tak
terdengar melewati hutan?dan juga Akio
harus tahu kalau ia datang sebagai utusan
Takeo.
Perjalanan itu membuat napasnya terasa
sesak, dan saat berhenti sebentar di tepi
sawah yang penuh air, terasa ada darah di
tenggorokannya. Tubuhnya terasa lebih
panas dari yang semestinya. Langit berubah
keemasan saat mentari mulai tenggelam di
ufuk barat. Pematang sawah berwarna cerah
dengan bunga liar, vicia, buttercup, dan
bunga krisan, dan cahaya matahari jatuh di
sela-sela hijaunya dedaunan. Suasana terasa
dipenuhi musik musim semi, nyanyian
burung, katak serta jangkrik.
Bila hari ini memang ditakdirkan menjadi
hari terakhir hidupku, maka tak ada hari yang
lebih indah daripada hari ini, pikir kenji
dengan sedikit bersyukur, dan merasakan
dengan lidahnya kapsul beracun yang terselip
rapi di bekas rongga gigi gerahamnya yang
sudah tanggal.
Kenji belum tahu tempat istimewa ini
sebelum Hisao lahir, enam belas tahun lalu
dan butuh waktu lima tahun untuk
menemukannya. Sejak saat itu, sesekali ia
mengunjungi tempat ini tanpa diketahui
penghuninya, dan mendapatkan laporan
tentang Hisao dari Taku, keponakan
buyutnya. Tempat ini sama seperti
kebanyakan desa Tribe: tersembunyi di
dalam lembah seperti lipatan kecil dalam
barisan pegunungan. Pada kunjungan yang
pertama ia sempat terkejut melihat ada lebih
dari dua ratus orang di desa itu. Tapi
kemudian ia tahu kalau keluarga Kikuta
mundur ke tempat ini sejak dikejar Takeo.
Mereka membangun desa di utara ini sebagai
markas, jauh dari jangkauan Takeo,
walaupun tidak di luar jangkauan mata-
matanya.
***
Hisao tidak berbicara pada siapa pun saat
mereka berjalan di antara rumah kayu
beratap rendah, dan meskipun beberapa
anjing melompat-lompat penuh semangat ke
arahnya, dia tak berhenti. Ketika sampai di
bangunan yang paling besar, orang ber-
kumpul di belakang mereka; Kenji men-
dengar bisik-bisik dan tahu kalau ia telah
dikenali.
Rumah itu jauh lebih nyaman dan mewah
ketimbang rumah-rumah di sekelilingnya,
dengan beranda dari kayu runjung serta pilar
kokoh dari kayu cedar. Seperti kuilnya, yang
bisa dilihat dari kejauhan, atapnya terbuat
dari rusuk atap yang tipis, dengan lekukan
luwes yang sama indahnya seperti kediaman
para ksatria. Seraya melepaskan sandal, Hisao
naik ke beranda dan berseru ke dalam rumah.
"Ayah! Kita kedatangan tamu!"
Selang beberapa saat, seorang perempuan
muda muncul, membawa air untuk
membasuh kaki sang tamu. Kerumunan
orang di belakang Kenji terdiam. Saat
melangkah masuk ke dalam rumah, ia seperti
mendengar tarikan napas tiba-tiba, seolah
semua orang yang berkumpul di luar
menarik napas di saat bersamaan. Dadanya
terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk dan rasanya
tak tahan ingin batuk. Betapa lemah tubuh-
nya saat ini! Teringat dengan rasa penyesalan
kalau semua kemampuan yang ia miliki kini
hanya menjadi bayang-bayang. Ia ingin sekali
meninggalkan raganya lalu pindah ke alam
baka, kehidupan yang lain, kehidupan apa
pun yang ada di sana. Andai ia bisa
menyelamatkan bocah itu... tapi siapa yang
bisa menyelamatkan orang dari takdir?
Semua pikiran ini melintas di benaknya
saat duduk di lantai berlapis karpet sambil
menunggu Akio. Ruangan itu remang-
remang: ia nyaris tidak bisa melihat gulungan
yang tergantung di dinding sebelah kanan-
nya. Perempuan muda yang sama datang
membawa semangkuk teh. Hisao sudah
pergi, namun terdengar olehnya anak itu
sedang bicara dengan pelan di belakang
rumah. Aroma minyak wijen merebak dari
arah dapur dan didengarnya desis makanan
di penggorengan. Lalu terdengar langkah
kaki; pintu banian dalam bergeser terbuka
dan Kikuta Akio melangkah masuk. Dia
diikuti dua laki-laki yang lebih tua, yang satu
bertubuh gempal dengan raut wajah halus
yang dikenal Kenji sebagai Gosaburo,
pedagang dari Matsue, adik Kotaro, paman
Akio. Sedang yang satunya lagi pasti Imai
Kazuo, yang menurut kabar telah menentang
keluarga Imai untuk tinggal bersama Kikuta,
keluarga dari pihak istrinya. Semua orang ini,
setahunya, sudah bertahun-tahun mengincar
dirinya.
Mereka berusaha menyembunyikan keter-
kejutan dengan kemunculannya. Mereka
duduk di ujung lain ruangan seraya meng-
amati. Tak seorang pun membungkuk
normal maupun memberi salam. Kenji pun
diam saja.
Akhirnya Akio angkat bicara, "Letakkan
senjatamu."
"Aku tak membawa senjata," sahut Kenji.
"Aku datang dengan membawa misi yang
damai."
Gosaburo tertawa sinis tidak percaya.
Sedang dua laki-laki lainnya tersenyum, tapi
tanpa rasa riang.
"Benar, seperti serigala di musim dingin,"
ujar Akio. "Kazuo yang akan menggeledah-
mu."
Kazuo mendekati Kenji dengan hati-hati
dan agak malu-malu. "Maaf, Ketua,"
gumamnya. Kenji membiarkan orang itu
meraba pakaiannya dengan jari-jarinya yang
panjang dan cekatan.
"Dia berkata jujur. Dia tidak membawa
senjata."
"Mengapa kau kemari?" sera Akio. "Rupa-
nya kau sudah bosan hidup!"
Kenji menatap tajam. Selama bertahun-
tahun ia bermimpi berhadapan dengan orang
yang telah menikahi dan terlibat dalam
kematian putrinya. Tampak ada kerutan-
kerutan di wajah Akio, rambutnya pun mulai
memutih. Tapi badannya tampak sekuat
baja; temyata usia tak mampu melunakkan
maupun melembutkan sikapnya.
"Aku datang membawa pesan dari Lord
Otori," tutur Kenji tenang.
"Kami tidak memanggilnya Lord Otori.
Dia dikenal dengan nama Otori si Anjing.
Kami tak ingin mendengar pesan apa pun
darinya!"
"Aku khawatir salah satu putramu sudah
mati," Kenji bicara pada Gosaburo. "Putra
sulungmu, Kunio. Tapi yang lainnya masih
hidup, termasuk putrimu."
Gosaburo menelan ludah. "Biarkan dia
bicara," katanya pada Akio.
"Kita tak mau beranding dengan Si
Anjing," sahut Akio.
"Dengan mengutus pembawa pesan itu
telah menunjukkan kelemahan," kata
Gosaburo dengan nada memohon. "Dia
sedang memohon pada kita. Setidaknya kita
dengar dulu apa yang akan Muto sampai-
kan." Gosaburo mencondongkan badan lalu
bertanya pada Kenji. "Putriku? Dia tidak
terluka?"
"Tidak, dia baik-baik saja." Tapi putriku
sudah mati enam belas tahun lalu.
"Dia tidak disiksa?"
"Kau harus tahu kalau penyiksaan kini
dilarang. Anak-anakmu akan diadili dengan
tuduhan percobaan pembunuhan, dan bisa
dihukum mati, tapi mereka tidak disiksa.
Kau tentu pernah mendengar bahwa Lord
Otori memiliki sifat welas asih."
"Satu lagi kebohongan dari Si Anjing,"
ejek Akio. "Tinggalkan kami, paman.
Kesedihan membuatmu lemah. Aku akan
bicara dengan Muto berdua saja."
"Anak-anak itu akan tetap hidup jika kau
setuju untuk berdamai," sahut Kenji cepat,
sebelum Gosaburo berdiri.
"Akio!" Gosaburo memohon, air mata
mulai berlinang.
"Tinggalkan kami!" Akio juga berdiri,
gusar, seraya mendorong tubuh orang tua itu
ke pintu, menyuruhnya agar cepat keluar dari
ruangan itu.
"Sejujurnya," katanya saat kembali duduk.
"Tua bangka bodoh itu tidak berguna lagi!
Dia sudah mis kin, dan yang kini dia lakukan
hanyalah meratap dan menyesali nasibnya.
Biarkan Otori membunuh anak-anak itu,
dan aku akan menghabisi ayahnya: kita akan
menyingkirkan orang lemah."
"Akio," tutur Kenji. "Kita bicara sebagai
sesama Ketua, sesuai cara Tribe menyelesai-
kan masalah. Dengar dulu apa yang akan
kusampaikan. Setelah itu baru kau putuskan
apa yang terbaik bagi Kikuta dan Tribe,
bukan berdasarkan kebencian dan amarah
pribadimu, karena ini akan menghancurkan
mereka dan dirimu. Mari kita ingat lagi
sejarah Tribe, bagaimana kita bisa bertahan
sejak dulu kala. Kita selalu bekerjasama
dengan para bangsawan yang hebat: jangan-
lah kita menentang Otori. Apa yang dilaku-
kannya di Tiga Negara baik adanya: disetujui
masyarakat, baik petani ataupun ksatria.
Masyarakat yang dibentuknya berjalan
lancar; rakyat bahagia; tak ada yang mati
kelaparan dan tak ada penyiksaan. Hentikan
permusuhanmu. Sebagai imbalannya, keluar-
ga Kikuta akan dimaafkan: Tribe akan ber-
satu lagi. Menguntungkan bagi kita semua."
Nada suaranya seakan mengandung sihir
yang membuat ruangan senyap dan semua
orang yang berada di luar bungkam. Kenji
tahu kalau Hisao sudah kembali dan sedang
berlutut tepat di balik pintu. Saat ia berhenti
bicara, dikumpulkan tenaga lalu membiarkan
gelombang tenaganya mengalir memenuhi
ruangan itu. Dirasakannya ketenangan
menyapu semua orang, mereka duduk
dengan mata setengah terpejam.
"Dasar penyihir tua bangka." Akio me-
mecahkan kesunyian dengan teriakan penuh
amarah. "Tua bangka licik. Kau tak bisa
menjebakku dengan kebohonganmu. Tadi
kau mengatakan Si Anjing melakukan hal
baik! Rakyat gembira! Apa untungnya semua
ini bagi Tribe? Kau sudah lemah seperti
Gosaburo. Ada apa dengan kalian, orang-
orang tua? Apakah Tribe membusuk dari
dalam? Andai Kotaro masih hidup! Tapi Si
Anjing membunuhnyadia membunuh
pemimpin keluarganya sendiri, pada siapa dia
harus menyerahkan hidupnya atas kejahatan
yang dia lakukan. Kau saksinya: kau men-
dengar sumpah si Anjing saat di Inuyama.
Dia melanggar sumpah itu jadi dia sudah
sepantasnya mati. Tapi dia malah mem-
bunuh Kotaro, Ketua dari keluarganya
dengan bantuannmu. Dia tidak bisa dimaaf-
kan. Dia harus mati!"
"Aku takkan berdebat tentang mana
tindakannya yang salah dan yang benar,"
sahut Kenji. "Dia melakukan apa yang harus
dilakukan saat itu, dan yang pasti, hidupnya
dijalani lebih baik sebagai Otori ketimbang
sebagai Kikuta. Tapi semua itu telah berlalu.
Kumohon kau hentikan perlawananmu agar
Kikuta bisa kembali ke Tiga Negara
Gosaburo bisa menjalankan lagi bisnisnya!
dan menikmati hidup selayaknya. Jika tetap
tak mau berdamai, maka menyerahlah: kau
takkan berhasil membunuhnya."
"Semua orang pasti mati," sahut Akio.
"Tapi dia takkan mati di tanganmu," ujar
Kenji. "Betapa pun kau menginginkannya.
Aku bisa meyakinkanmu akan hal itu."
Akio menatapnya dengan memicingkan
mata. "Pengkhianatanmu pada Tribe harus
dihukum."
"Aku telah melindungi keluargaku dan
Tribe. Kau yang menghancurkannya. Aku
kemari sebagai utusan, dan aku akan kembali
dengan cara yang sama. Akan kusampaikan
pesanmu yang patut disesalkan pada Lord
Otori."
Kenji begitu berwibawa sehingga Akio
membiarkannya berdiri lalu berjalan keluar
ruangan. Sewaktu lewat Hisao masih berlutut
di luar, Kenji berkata, seraya membalikkan
badan, "Ini putramu? Kurasa dia tidak
memiliki kemampuan Tribe. Ijinkan dia
menemaniku sampai ke gerbang. Mari,
Hisao." Kenji bicara ke belakang dalam
bayang-bayang. "Kau tahu di mana bisa
menemukan kami bila kau berubah pikiran."
Baiklah, pikimya saat melangkah keluar
dari beranda dan kerumunan memberi jalan
padanya, ternyata aku masih hidup lebih lama.
Begitu sampai di tempat terbuka dan di luar
jangkauan tatapan Akio, ia bisa saja
menghilang lalu melenyapkan diri ke
pedesaan. Tapi adakah peluang ia membawa
bocah itu?
Penolakan Akio tidak mengejutkannya.
Tapi ia senang Gosaburo dan yang lainnya
juga mendengar. Selain rumah utama, desa
itu kelihatan menyedihkan. Pasti sulit men-
jalani hidup di sini, apalagi di musim dingin.
Kebanyakan penghuninya pasti mendamba-
kan, seperti halnya Gosaburo, hidup nyaman
di Matsue dan Inuyama. Kepatuhan mereka
pada Akio, dirasakan oleh Kenji, lebih karena
ketakutan ketimbang rasa hormat; ada
kemungkinan anggota lain Kikuta me-
nentang keputusannya, apalagi jika itu
berarti sandera akan dibiarkan hidup.
Saat Hisao muncul dari belakang dan
berjalan di sampingnya, Kenji menyadari ada
kehadiran lain yang mengambil tempat
setengah tubuh dan pikiran bocah itu. Dahi-
nya berkerut, dan sesekali menaikkan tangan-
nya memegangi pelipis kirinya dengan ujung
jari. "Kepalamu sakit?"
"Mmm." Dia mengangguk tanpa bicara.
Mereka sudah separuh jalan. Bila berhasil
sampai di tepi sawah, lalu berlari di
pematang ke hutan bambu....
"Hisao," bisik Kenji. "Aku ingin kau ikut
denganku ke Inuyama. Temui aku di tempat
tadi kita bertemu. Kau mau?"
"Aku tak bisa pergi dari sini! Aku tak bisa
meninggalkan ayahku!" Lalu ia berseru
kesakitan, lalu terjatuh.
Hanya tinggal lima puluh langkah lagi.
Kenji tidak berani berbalik, tapi ia yakin tak
ada yang mengikutinya. la terus berjalan
dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, tapi Hisao
berjalan terseok-seok di belakangnya.
Saat berbalik untuk memberi Hisao
semangat, Kenji melihat kerumunan orang
masih memerhatikan. Tiba-tiba ada yang
menyeruak dari sela-sela mereka. Akio,
diikuti oleh Kazuo: keduanya sudah menarik
belati.
"Hisao, temui aku," katanya, lalu meng-
hilang, tapi ketika sosok tubuhnya
menghilang, Hisao menangkap lengannya
dan berteriak, "Bawa aku! Mereka takkan
membiarkanku pergi! Tapi dia ingin ikut
denganmu!"
Mungkin karena Kenji sedang dalam
keadaan menghilang dan berada di antara
dua dunia, mungkin juga karena perasaan
Hisao yang meledak-ledak, tapi saat itu Kenji
melihat apa yang Hisao lihat....
Putrinya, Yuki. Meninggal enam belas
tahun lalu....
Lalu menyadari dengan rasa takjub
kemampuan sebenarnya bocah itu.
Seorang penguasa alam baka.
Kenji belum pernah bertemu orang
dengan kemampuan ini: dia hanya tahu dari
hikayat-hikayat Tribe. Hisao sendiri tidak
mengetahuinya, begitu juga Akio. Akio tidak
boleh tahu.
Tak heran kalau bocah itu sering sakit
kepala. Ia ingin tenawa, sekaligus menangis.
Kenji masih merasakan cengkeraman
Hisao di tangannya saat ia menatap wajah
arwah putrinya, melihat putrinya saat masih
kanak-kanak, remaja. Kian lama wajah
putrinya kian melemah dan samar-samar.
Dilihat bibir putrinya bergerak-gerak dan
berkata, "Ayah," walaupun Yuki tidak pernah
lagi memanggilnya dengan sebutan itu sejak
berusia sepuluh tahun.
Saat ini Yuki membuatnya terpesona,
seperti yang selalu dilakukannya.
"Yuki," katanya tak berdaya, dan mem-
biarkan dirinya terlihat lagi.
***
Terbukti mudah bagi Akio dan Kazuo untuk
mendekati Keji. Tak satu pun kemampuan
menghilangkan diri maupun menggunakan
sosok kedua yang dapat menyelamatkan diri-
nya dari mereka berdua.
"Dia tahu bagaimana menangkap Otori,"
seru Akio. "Kita akan tahu itu darinya,
kemudian Hisao harus membunuhnya."
Tapi Kenji sudah menggigit racun lalu
mencerna dalam perutnya: ramuan yang
pernah dipaksakan pada putrinya untuk
ditelan. Kenji mati dengan cara yang sama,
penuh penderitaan dan penyesalan karena
misinya gagal dan juga karena meninggalkan
cucunya. Di saat-saat terakhir dia berdoa agar
bisa tinggal bersama arwah putrinya, agar
Hisao memanfaatkan kekuatan dirinya untuk
menjaganya: Tak terbayangkan betapa hebat-
nya diriku sebagai hantu, pikirnya. Lalu ia
tertawa: hidupnya yang penuh penderitaan
dan kebahagiaan telah berakhir. Tugasnya di
dunia sudah selesai, dan dia mati atas
keinginannya sendiri. Rohnya bebas bergerak
memasuki siklus abadi dari kelahiran,
kematian dan kelahiran kembali.*
Musim dingin di Inuyama terasa panjang dan
berat, walau ada kesenangan tersendiri:
selama itu Kaede menghabiskan waktu
dengan membacakan puisi dan dongeng
untuk ketiga putrinya. Takeo menghabiskan
waktu dengan melihat-lihat catatan adminis-
trasi bersama Sonoda. Saat ingin bersantai, ia
mempelajari lukisan bersama seorang
seniman beraliran tinta hitam, dan minum
bersama Kenji di malam harinya: Ketiga
putrinya disibukkan dengan belajar dan
berlatih, ada juga rekreasi saat Setsubun,
perayaan yang ramai dan semarak saat setan
diusir keluar dari rumah dan menyambut
nasib baik. Juga ada perayaan usia akil balik
Shigeko karena pada Tahun Baru dia berusia
lima belas tahun. Perayaannya tidak mewah
karena pada bulan kesepuluh nanti dia akan
diserahkan wilayah Maruyama. Wilayah itu
diwariskan melalui garis perempuan dan
telah diwariskan kepada ibunya, Kaede,
setelah kematian Maruyama Naomi.
Kelak Shigeko akan menjadi penguasa
Tiga Negara, dan kedua orangtuanya sepakat
bahwa dia harus memimpin wilayah
Maruyama tahun ini karena saat ini dia telah
dewasa. Di sana dia harus membuktikan diri
sebagai penguasa dan belajar secara langsung
tentang prinsip-prinsip pemerintahan.
Upacara di Maruyama nanti akan dilakukan
dengan khidmat sekaligus megah, menguat-
kan tradisi dan, Takeo berharap, memantap-
kan keputusan baru: perempuan dapat me-
warisi wilayah atau menjadi pemimpin desa,
sederajat dengan laki-laki.
Takeo teringat, saat keluarganya ter-
lindungi dari kedinginan dan rasa bosan
selama musim dingin yang panjang, dua
pemuda yang tidak terlalu berbeda jauh
usianya dengan putrinya, ditahan di kastil
Inuyama. Meskipun diperlakukan dengan
baik, namun tetap saja mereka adalah
tawanan.
Setelah salju mencair, dan Kenji berangkat
melaksanakan misinya, Kaede serta putri-
putrinya pergi ke Hagi bersama Shizuka.
Takeo melihat kegelisahan istrinya pada si
kembar semakin bertambah. Ia memikirkan
kemungkinan Shizuka mengajak salah satu
dari mereka, mungkin Maya, ke desa ter-
sembunyi Muto, Kagemura selama beberapa
minggu. Takeo pun menunda waktu untuk
meninggalkan Inuyama, berharap mendapat
kabar dari Kenji di bulan ini. Namun ketika
hingga bulan keempat muncul dan masih
belum ada kabar, dengan enggan ia pergi ke
Hofu. Ia memberi instruksi agar Taku
mengirimkan semua pesan kepadanya di
sana.
Selama berkuasa, ia sering melakukan per-
jalanan, membagi hari-hari dalam setahun
dari satu kota ke kota lainnya di Tiga
Negara. Kadang ia melakukan perjalanan
dengan semua kemegahan yang diharapkan
dari seorang penguasa besar, kadang ia
menyamar untuk dapat berbaur dengan
rakyat biasa dan mengetahui pendapat,
kegembiraan serta kebahagiaan mereka.
Takeo tidak akan melupakan kata-kata Otori
Shigeru kepadanya: Karena Kaisar yang
begitu lemah sehingga bangsawan seperti Iida
bisa merajalela. Sebenarnya kaisar berkuasa
atas Delapan Pulau, namun dalam
pelaksanaannya, berbagai daerah mengurus
masalah mereka sendiri: Tiga Negara dilanda
konflik akibat para bangsawan berebut
wilayah dan kekuasaan. Kini ia dan Kaede
telah membawa kedamaian dan memper-
tahankannya dengan penuh perhatian pada
seluruh wilayah dan berbagai aspek ke-
hidupan rakyatnya.
Hasil dari semua itu terlihat saat ia ber-
kuda ke wilayah Barat. Didampingi para
pengawal, dua pengawal terpercaya dari
Tribe saudara sepupu Kuroda: Junpei dan
Shinsaku, yang dikenal sebagai Jun dan
Shinserta jurutulisnya. Selama perjalanan
ia memerhatikan tanda-tanda negeri yang
damai: anak-anak yang sehat, desa yang
makmur, sedikit pengemis serta tidak ada
bandit. Tujuannya untuk membuat negara
ini sangat aman hingga gadis belia pun bisa
memegang kekuasaan, dan ketika tiba di
Hofu, ia bangga dan puas bahwa Tiga
Negara telah sesuai dengan tujuannya itu.
Ia tidak menduga apa yang menantinya di
kota pelabuhan itu, ataupun curiga kalau di
sana nanti kepercayaan dirinya akan goyah
dan kekuasaannya terancam.
***
Tampaknya begitu ia tiba di kota mana pun
di Tiga Negara, utusan bermunculan di
gerbang kastil atau kediaman ia tinggal: ingin
mengadakan pertemuan, meminta bantuan,
membutuhkan keputusan yang hanya bisa
diputuskan olehnya. Beberapa dari masalah
ini sebenarnya dapat disampaikan pada
petugas setempat, tapi terkadang ada keluhan
atas para petugas itu sehingga hakim-hakim
yang adil harus didatangkan. Musim semi
ini, di Hofu, ada tiga mau empat kasus
semacam ini, lebih dari yang Takeo harap-
kan. Hal ini membuatnya mempertanyakan
keadilan dari administrasi setempat. Bahkan
dua petani mengeluh kalau putra mereka
dipaksa menjadi prajurit, dan seorang
pedagang memberi informasi bahwa para
prajurit menyita sejumlah besar batu bara,
kayu, belerang dan nitrat. Zenko tengah
menghimpun kekuatan dan senjata, pikirnya.
Aku harus bicara padanya.
Takeo mengatur untuk mengirim kurir ke
Kumamoto. Namun, keesokan harinya Arai
Zenkoyang telah diberi bekas wilayah
ayahnya di bagian Barat dan juga Hofu
datang dari Kumamoto dengan alasan
hendak menyambut Lord Otori. Istrinya,
Shirakawa Hana, adik bungsu Kaede, ikut
bersamanya. Hana sangat mirip dengan
kakak sulungnya, bahkan bila diperhatikan
lebih lama lagi kelihatan lebih cantik di-
bandingkan Kaede saat masih muda. Ia tidak
suka maupun percaya pada Hana. Sepanjang
tahun yang sulit setelah kelahiran si kembar,
saat empat belas tahun, Hana selalu mencari
kesempatan untuk menggoda dirinya agar
menjadikannya istri kedua atau selir. Hana
menjadi lebih dari sekadar godaan yang bisa
diakui Takeo, dengan paras yang sama persis
seperti Kaede muda, sebelum kecantikannya
tercoreng. Bahkan Hana pernah menawarkan
diri ketika kesehatan Kaede memburuk.
Penolakan mantap Takeo untuk menganggap
serius tawarannya telah melukai dan mem-
permalukan Hana: keinginan Takeo untuk
menikahkannya dengan Zenko justru mem-
buat Hana kian gusar. Tapi Takeo memaksa:
mereka menikah ketika Zenko berusia
delapan belas tahun dan Hana enam belas
tahun. Zenko sangat senang: persekutuan itu
merupakan kehormatan besar baginya; Hana
bukan hanya cantik, tapi juga segera mem-
berinya tiga putra, semuanya sehat. Rasa
tergila-gilanya pada Takeo segera digantikan
rasa dendam padanya dan iri pada kakaknya.
Dia pun bertekad untuk mengambil alih
kedudukan mereka.
Takeo tahu niat ini karena adik iparnya
lupa kalau ia memiliki pendengaran yang
sangat peka. Pendengarannya memang tidak
setajam saat masih tujuh belas tahun, tapi
masih cukup baik untuk menguping per-
cakapan rahasia, menyadari segala sesuatu
yang ada di sekelilingnya, di mana posisi tiap
orang di kastil, kegiatan mereka yang ada di
pos jaga dan istal, siapa mengunjungi siapa di
malam hari dan untuk tujuan apa. Ia juga
dapat membaca niat orang itu dari cara ber-
diri hingga gerakan tubuh.
Saat ini ia mengamati Hana yang sedang
membungkuk di hadapannya, dengan
rambut menjuntai ke lantai, sedikit tersibak
hingga menampakkan tengkuknya yang
putih sempurna. Hana bergerak dengan
luwes, terlepas dari kenyataan bahwa dia
adalah ibu dari tiga orang anak: orang akan
mengira usianya tak lebih dari delapan belas
tahun, tapi sebenarnya dia seumur dengan
adik Zenko, Taku: dua puluh enam tahun.
Suaminya, di usia dua puluh delapan
tahun, tampak sangat mirip dengan ayahnya:
bertubuh besar, gagah perkasa, bertenaga
besar, ahli menggunakan panah dan pedang.
Pada usia dua belas tahun dia menyaksikan
ayahnya mati ditembak dengan senjata api,
orang ketiga di Tiga Negara yang mati
dengan cara begitu. Dua orang lainnya
adalah para bandit. Ia menyadari bila semua
ini dijadikan satu maka bisa menimbulkan
sakit hati yang mendalam pada pemuda itu,
dan bisa berubah menjadi kebencian.
Kedua orang ini tidak menunjukkan
tanda-tanda kedengkian. Sambutan dan
pertanyaan mereka mengenai kesehatan diri
juga keluarganya terasa berlebihan. Ia
menjawab dengan sikap yang sama sopannya,
menutupi kenyataan kalau ia merasa lebih
kesakitan ketimbang biasanya karena udara
yang lembap.
"Kalian tidak perlu repot-repot datang,"
katanya. "Aku hanya akan berada di Hofu
selama satu atau dua hari."
"Oh, tapi Lord Takeo harus tinggal lebih
lama." Hana angkat bicara, seperti yang
sering dia lakukan sebelum suaminya sempat
bicara. "Anda harus tinggal di sini sampai
musim hujan selesai. Anda tidak bisa
bepergian dalam keadaan cuaca seperti ini."
"Aku pernah melakukan perjalanan dalam
cuaca yang lebih buruk," sahut Takeo sambil
tersenyum.
"Kami senang bisa menghabiskan waktu
bersama kakak ipar," kata Zenko.
"Baiklah, ada satu atau dua hal yang perlu
kita bicarakan," sahut Takeo, memutuskan
untuk menanggapi basa-basi ini. "Tidak ada
kebutuhan, pastinya, untuk meningkatkan
jumlah pasukan, dan aku ingin tahu lebih
banyak tentang kekuatan apa yang sedang
kau himpun."
Keterusterangannya yang keluar tepat
setelah sopan-santun tadi, mengejutkan
mereka. Takeo tersenyum lagi. Mereka pasti
tahu, tak banyak hal yang bisa luput dari
perhatiannya di seluruh Tiga Negara.
"Kebutuhan senjata selalu ada," tutur
Zenko. "Tombak, pedang, panah dan
sebagainya."
"Berapa banyak orang yang kau kumpul-
kan? Paling banyak lima ribu orang. Catatan
kami menunjukkan mereka semua diper-
senjatai. Bila senjata mereka hilang atau
rusak, maka mereka harus menggantinya
dengan biaya sendiri. Keuangan wilayah bisa
dijalankan dengan baik."
"Dari Kumamoto dan distrik selatan, ya,
benar lima ribu orang. Tapi ada banyak
orang yang tidak terlatih dengan usia cukup
untuk bertempur di wilayah Seishuu lainnya.
Tampaknya ini kesempatan emas untuk
memberi mereka pelatihan dan senjata,
bahkan jika mereka kembali ke sawahnya
untuk panen."
"Klan Seishuu kini tunduk pada
Maruyama," sahut Takeo dengan nada
ringan. "Bagaimana pendapat Sugita Hiroshi
tentang rencanamu?"
Hiroshi dan Zenko tidak menyukai satu
sama lain. Takeo tahu Hiroshi memendam
hasrat untuk menikahi Hana, dan kecewa
ketika perempuan idamannya itu menikah
dengan Arai Zenko, walaupun Hiroshi tidak
pernah mengatakannya. Kedua pemuda itu
tidak saling menyukai sejak pertama kali
mereka bertemu bertahun-tahun silam
semasa perang saudara. Hiroshi dan Taku,
adik Zenko, adalah teman dekat, jauh lebih
dekat ketimbang. Kedua kakak beradik yang
semakin dingin.
"Aku belum sempat bicara dengan Sugita,"
aku Zenko.
"Baiklah, kelak kita bicarakan masalah ini
dengannya.
Nanti kita semua akan bertemu di
Maruyama pada bulan kesepuluh dan meng-
kaji ulang kebutuhan pasukan di wilayah
Barat."
"Kita menghadapi ancaman dari kaum
barbar," tutur Zenko. "Wilayah Barat
terbuka lebar bagi mereka: Klan Snshuu
belum pernah menghadapi serangan dari
laut. Kami tidak siap."
"Tujuan orang-orang asing itu sebenarnya
hanyalah berdagang," sahut Takeo. "Mereka
berada jauh dari kampung halaman mereka,
kapal-kapal mereka kecil. Mereka mestinya
jera dengan serangan di Mijima; maka
sekarang mereka harus berurusan dengan kita
melalui diplomasi. Pertahanan terbaik kita
melawan mereka adalah berdagang dengan
damai."
"Tapi mereka selalu membual tentang
pasukan hebat raja mereka," timpal Hana.
"Seribu orang bersenjata api. Lima puluh
ribu kuda. Satu ekor kuda mereka lebih besar
dibandingkan dua ekor kuda kita, kata
mereka. Dan pasukan pejalan kaki mereka
menyandang senjata api."
"Semua ini, seperti yang kau katakan,
hanyalah bualan," Takeo mengamati. "Aku
berani katakan kalau Terada Fumio mem-
buat pernyataan serupa tentang keunggulan
kita di kepulauan wilayah Barat dan
pelabuhan di Tenjiku dan Shin." Dilihatnya
ekspresi wajah Zenko berkerut saat nama
Fumio disebut. Fumio yang menembak ayah
Zenko saat gempa mengguncang dan meng-
hancurkan pasukan Arai. Takeo menghela
napas panjang, ingin tahu apakah mungkin
menghapuskan keinginan balas dendam
Zenko.
Zenko berkata, "Di sana kaum barbar juga
menggunakan perdagangan sebagai alasan
untuk menjejakkan kaki. Lalu mereka
melemahkan dari dalam dengan agama
mereka, dan serangan dari luar. Mereka akan
mengubah kita semua menjadi budak
mereka."
Zenko mungkin benar, pikir Takeo. Orang-
orang asing itu sebagian besar terkurung di
Hofu, dan Zenko bertemu dengan lebih
banyak orang-orang itu ketimbang ksatria-
nya sendiri. Kendati menyebut dengan kata
kaum barbar, Zenko tampak terkesan dengan
senjata dan kapal mereka. Seandainya mereka
bergabung di wilayah Barat...
"Kau tahu kalau aku menghormati
pendapatmu dalam masalah ini," sahutnya.
"Akan kita tingkatkan pengawasan terhadap
orang-orang asing itu. Apabila nanti diperlu-
kan lebih banyak pasukan, akan kuberitahu-
kan kepadamu. Dan nitrat hanya boleh dibeli
langsung oleh klan."
Takeo memerhatikan selagi Zenko mem-
bungkuk dengan enggan, segaris rona warna
di lehernya menandakan kekesalannya atas
peringatan keras tadi. Takeo teringat saat
menempelkan pisau di leher Zenko. Kalau
saja saat itu ia menggunakan pisau dengan
baik, ia bisa terhindar dari banyak masalah.
Namun kala itu Zenko hanyalah bocah kecil;
ia belum pernah membunuh anak-anak dan
berdoa semoga tidak akan pernah. Zenko
adalah bagian dari takdirku, pikirnya. Aku
harus hadapi dia dengan hati-hati. Apa lagi
yang bisa kulakukan untuk menjinakkan
dirinya?
Hana berkata dengan suara selembut
madu. "Kami takkan melakukan apa pun
tanpa berkonsultasi dengan Lord Otori.
Sesungguhnya kami hanya menaruh per-
hatian pada Anda sekeluarga serta kemak-
muran Tiga Negara. Anda sehat-sehat saja,
kurasa. Bagaimana dengan kakak sulungku,
juga ketiga putri Anda yang cantik-cantik?"
"Terima kasih: mereka semua sehat-sehat
saja."
"Satu kesedihan yang mendalam bagiku
karena tidak punya anak perempuan," lanjut
Hana, tatapan matanya lenang, serius dan
agak malu-malu. "Seperti yang Lord Otori
ketahui, kami hanya punya anak laki-laki."
Mau ke mana arah pembicaraannya? Takeo
penasaran.
Zenko yang kurang memiliki kehalusan
dalam berbicara dibandingkan istrinya lalu
bicara dengan nada datar.
"Lord Otori pasti sangat ingin memiliki
putra."
Ah! pikir Takeo, lalu berkata, "Karena
sepertiga negara kiia sudah diwariskan
melalui garis keturunan perempuan, hal itu
tak menjadi masalah. Putri sulung kami pada
akhirnya akan menjadi penguasa Tiga
Negara."
"Tapi Anda harus tahu kebahagiaan
memiliki anak laki-laki," seru Hana. "Ijinkan
kami memberikan salah satu putra kami."
"Kami ingin Anda mengangkat salah satu
putra kami," ujar Zenko, tanpa basa-basi.
"Sungguh itu suatu kehormatan besar serta
membawa kebahagiaan tak terbilang bagi
kami," gumam Hana.
"Kalian sangat murah hati dan penuh
pengertian," sahut Takeo. Kebenarannya
adalah: ia tak ingin anak laki-laki. Ia lega
Kaede tidak melahirkan lagi dan berharap
istrinya tidak hamil lagi. Ramalan bahwa ia
akan mati di tangan putranya sendiri tidaklah
menakutkan, namun menorehkan kesedihan
mendalam pada dirinya. Saat itu Takeo
berdoa, seperti yang sering dilakukannya,
kalau kematiannya seperti kematian Shigeru,
bukan seperti pemimpin Otori yang lain,
Masahiro, yang mati digorok oleh anak
haramnya. Ia juga berdoa dibiarkan hidup
hingga tugasnya selesai dan putrinya telah
cukup dewasa untuk memerintah negeri ini.
Karena tak ingin menghina mereka dengan
langsung menolak tawaran itu. Sesungguh-
nya amat pantas mengangkat keponakan
istrinya: bahkan mungkin kelak ia bisa
menjodohkan anak itu dengan salah satu
putrinya.
"Mohon kami diberi kehormatan dengan
menerima dua putra tertua kami," tutur
Hana. Ketika Takeo mengangguk setuju,
Hana bangkit dan berjalan ke pintu dengan
luwes, sangat mirip dengan Kaede. Lalu
masuk kembali bersama kedua anaknya: usia
mereka delapan dan enam tahun, mengena-
kan jubah resmi, diam terpaku dengan
khidmat dalam pertemuan itu. Rambut
mereka ditata dengan bagian rambut yang
panjang di bagian depan.
"Yang sulung bernama Sunaomi, sedang
adiknya, Chikara," tutur Hana selagi kedua
bocah itu membungkuk sampai ke lantai di
hadapan paman mereka.
"Ya, aku ingat," sahut Takeo. Sudah tiga
tahun ia belum bertemu kedua bocah ini,
dan belum pernah bertemu putra bungsu
Hana yang lahir tahun lalu. Kedua anak itu
tampan: yang sulung mirip dengan Shira-
kawa bersaudara, dengan tulang punggung
yang panjang serta struktur tulang yang
ramping. Sedangkan adiknya lebih bulat dan
kekar, lebih mirip ayahnya. Takeo ingin tahu
apakah salah satu dari mereka mewarisi
kemampuan Tribe dari neneknya, Shizuka.
Nanti akan ditanyakannya pada Taku atau
Shizuka. Akan menyenangkan, renungnya,
bagi Shizuka untuk mengasuh cucunya.
"Duduk tegak, anak-anak," kata Takeo.
"Biarkan paman melihat wajah kalian."
Takeo tertarik pada si sulung yang amat
mirip Kaede. Usianya hanya tujuh tahun
lebih muda dari Shigeko, dan lima tahun
lebih muda dari Maya dan Miki: perbedaan
ini bukanlah masalah dalam perkawinan.
Diajukannya pertanyaan tentang pelajaran,
kemajuan berpedang dan memanah, dan
senang dengan jawaban mereka yang cerdas
serta jelas. Apa pun ambisi tersembunyi dan
motif terselubung dari orangtua mereka,
kedua bocah ini telah dididik dengan baik.
"Kalian sangat murah hati," ujar Takeo
lagi. "Aku akan membicarakannya dengan
istriku."
"Anak-anak akan bergabung bersama kita
saat makan malam," ujar Hana. "Anda bisa
lebih mengenal mereka nanti. Tentu saja,
Sunaomi sudah menjadi kesayangan kakak
sulungku."
Kini Takeo ingat kalau ia pernah men-
dengar Kaede memuji Sunaomi karena
kecerdasannya. Ia tahu istrinya iri pada Hana
dan menyesal karena tidak punya anak laki-
laki. Mengangkat keponakannya mungkin
bisa menjadi kompensasi, tapi jika Sunaomi
menjadi putranya...
Disingkirkannya pikiran itu jauh-jauh. Ia
harus memutuskan yang terbaik saat ini:
jangan sampai ia terpengaruh oleh ramalan
yang mungkin saja tidak akan terjadi.
Ketika Hana pergi bersama kedua anak-
nya, Zenko berkata, "Aku ingin ulangi kalau
ini akan menjadi kehormatan bagi kami bila
Anda mengangkat Sunaomiatau Chikara:
Anda harus memilih."
"Kita bicarakan ini pada bulan kesepuluh."
"Bolehkah aku mengajukan satu
permohonan lagi?"
Ketika Takeo mengangguk, Zenko
melanjutkan, "Aku tak ingin menyinggung
perasaan dengan mengingat masa lalu, tapi
Anda ingat Lord Fujiwara?"
"Tentu saja," jawab Takeo, menahan rasa
kaget dan marah. Lord Fujiwara adalah
bangsawan yang telah menculik istrinya.
Bangsawan itu mati dalam bencana gempa
tapi Takeo tidak pernah memaafkannya.
Kaede telah bersumpah bahwa bangsawan itu
tak pernah tidur dengannya, namun ada
semacam ikatan aneh antara mereka berdua;
Fujiwara telah memikat dan menyanjungnya;
Kaede telah membuat perjanjian dengan laki-
laki itu dan menceritakan rahasia paling
pribadi tentang cinta Takeo. Juga pernah
membantu keluarga Kaede dengan uang,
makanan, juga banyak hadiah. Fujiwara
menikahi Kaede dengan restu Kaisar.
Fujiwara pernah berusaha agar Kaede mati
bersamanya: Kaede berhasil lolos walaupun
rambutnya terbakar, menyebabkan bekas
luka, kehilangan kecantikannya.
"Putranya berada di Hofu dan ingin ber-
temu secara resmi dengan Anda."
Takeo tidak berkata sepatah kata pun,
enggan untuk mengakui kalau ia tidak
mengetahuinya.
"Dia menggunakan nama keluarga ibunya,
Kono. Tiba dengan kapal beberapa hari lalu,
berharap bisa bertemu Anda. Kami telah ber-
hubungan melalui surat tentang hana warisan
ayahnya. Ayahku, seperti yang Anda tahu,
berhubungan baik dengan ayahnyaaku
mohon maaf telah membuat Anda teringat
masa-masa yang tak menyenangkandan
Lord Kono membicarakan tentang masalah
penyewaan dan pajak."
"Sepanjang ingatanku, harta Fujiwara
telah digabungkan dengan wilayah Shira-
kawa."
"Secara hukum Shirakawa juga merupakan
milik Fujiwara, setelah pernikahannya, maka
kini menjadi milik putranya. Karena
Fujiwara diwariskan melalui garis keturunan
laki-laki. Jika wilayah itu bukan hak Kono,
maka seharusnya diteruskan pada pewaris
laki-laki berikutnya."
"Yaitu putra sulungmu, Sunaomi," timpal
Takeo.
Zenko menunduk tanpa bicara.
"Enam belas tahun telah berlalu sejak
kematian ayahnya. Mengapa kini dia tiba-
tiba muncul?" tanya Takeo.
"Waktu berlalu dengan cepat di ibukota,"
sahut Zenko. "Dia utusan Yang Mulia
Kaisar."
Atau barangkali karena seseorang punya
rencana jahat, kau atau istrimuhampir pasti
istrimumelihat bagaimana Kono bisa
dimanfaatkan untuk lebih menekanku, maka
Kono dihubungi melalui surat, pikir Takeo,
menyembunyikan kemarahannya.
Hujan semakin deras menerpa atap, dan
bau tanah yang basah mengapung di depan
taman.
"Dia boleh datang dan bertemu denganku
besok," kata Takeo akhirnya.
"Ya. Keputusan yang bijaksana," sahut
Zenko. "Lagi pula jalan terlalu becek dan
berlumpur untuk meneruskan perjalanan."
***
Pertemuan ini semakin menambah ke-
gelisahan Takeo, mengingatkannya betapa
Arai Zenko sangat perlu diawasi: betapa
mudahnya ambisi mereka dapat menggiring
Tiga Negara kembali perang saudara. Sore
berlalu dengan suasana cukup menyenang-
kan: ia minum sake secukupnya untuk
menyembunyikan rasa sakit, dan kedua anak
laki-laki itu menghidupkan suasana dan
menghibur. Meteka baru saja bertemu
dengan dua orang asing di ruangan ini dan
sangat bersemangat dengan pertemuan itu:
bagaimana Sunaomi bicara pada mereka
dengan menggunakan bahasa mereka yang
telah dipelajari bersama ibunya; bagaimana
orang-orang asing itu kelihatan seperti goblin
dengan hidung panjang dan janggut lebat-
nya, yang satu berambut merah sedangkan
yang lainnya berambut hitam, tapi Chikara
sama sekali tidak takut. Mereka memerintah-
kan para pelayan untuk mengambilkan salah
satu kursi yang dibuat oleh orang asing dari
kayu eksotis, jati, dibawa dari pelabuhan
pedagangan besar yang dikenal dengan nama
Fragrant Harbour dalam kekuasaan kapal
nana milik Terada yang juga membawa
mangkuk jasper, lapis lazuli, kulit macan,
gading dan giok menuju kota-kota di Tiga
Negara.
"Sangat nyaman," ujar Sunaomi, mem-
peragakan.
"Agak mirip tahta Kaisar," kata Hana,
tertawa.
"Tapi mereka tidak makan menggunakan
tangan!" kata Chikara, kecewa. "Aku ingin
melihatnya."
"Mereka belajar sopan santun dari bangsa
kita," tutur Hana. "Mereka berusaha keras,
sama kerasnya dengan usaha Lord Joao mem-
pelajari bahasa kita."
Takeo agak merinding mendengar nama
itu, sangat mirip dengan nama gelandangan
Jo-An. Ia begitu menyesali tindakannya yang
telah memenggal Jo-An, dan pengemis itu
sering hadir dalam mimpinya. Orang-orang
asing itu memiliki kepercayaan yang serupa
dengan kepercayaan kaum Hidden dan ber-
doa pada Tuhan Rahasia. Bedanya, orang-
orang asing itu mempraktikannya secara ter-
buka, hingga membuat orang lain gelisah dan
malu. Mereka memperlihatkan lambang
Hidden, salib, pada untaian kalung yang
menggantung di dada pakaian mereka yang
aneh dan tidak nyaman. Bahkan di hari yang
paling panas pun mereka tetap memakai
pakaian ketat dengan kerah tinggi dan sepatu
bot, dan mereka memiliki ketakutan yang
tidak wajar untuk mandi.
Kini Jo-An telah menjadi semacam dewa,
terkadang salah ditafsirkan wujud Sang
Pencerah: dia disembah oleh orang-orang
miskin dan tunawisma. Hanya sedikit orang
yang tahu siapa Jo-An dulunya atau ingat apa
saja yang pernah dilakukan, namun namanya
telah terikat dengan peraturan yang meng-
atur pajak dan kewajiban masuk militer. Tak
satu pun pemilik tanah diperbolehkan
mengambil lebih dari tiga puluh bagian dari
seratus bagian atas number daya apa pun,
baik berupa beras, kedelai atau mniyak. Dan
kewajiban militer tidak dikenakan pada putra
petani, meskipun mendapat tugas untuk
menangani sarana umum tertentu, misalnya
mengeringkan tanah, membangun ben-
dungan dan jembatan serta menggali saluran.
Pertambangan juga merupakan pekerjaan
wajib; karena pekerjaan ini sangat berat dan
berbahaya hingga hanya sedikit orang yang
mau melakukannya; namun semua bentuk
pekerjaan wajib dirotasi ke seluruh distrik
dan kelompok usia agar tidak ada orang yang
harus memikul beban yang tidak adil.
Berbagai tingkat kompensasi diatur untuk
menggantikan kematian atau kecelakaan. Ini
semua dikenal dengan Hukum Jo-An.
Orang-orang asing bersemangat mem-
bicarakan tentang agama mereka, dan ketika
Takeo dengan hati-hati mengatur pertemuan
dengan Makoto dan pemimpin agama lain-
nya, tapi semua pertemuan ini berakhir
dengan cara yang sama, dengan kedua belah
pihak yakin dengan posisi mereka masing-
masing, ingin tahu secara pribadi bagaimana
ada orang lain bisa percaya pada omong
kosong lawan bicaranya. Kepercayaan orang-
orang asing, pikir Takeo, berasal dari sumber
yang sama dari kaum Hidden namun
ditambah dengan takhayul dan perubahan
bentuk selama berabad-abad. Ia sendiri
dibesarkan dalam tradisi Hidden namun
telah mengabaikan semua ajaran masa
kecilnya dan memandang semua ajaran
agama dengan kecurigaan dan keraguan,
terutama agama orang asing karena baginya
agama itu berhubungan dengan ketamakan
mereka pada kekayaan, status serta kekuasa-
an.
Satu ajaran yang paling menyita pikiran-
nyayaitu dilarang untuk membunuh
tampaknya tidak menjadi bagian dalam
kepercayaan mereka, karena mereka datang
bersenjata lengkap dengan pedang tipis
panjang, belati, pedang pendek dan tentu
saja senjata api. Ketika kecil, Takeo diajarkan
bahwa membunuh adalah dosa, bahkan
untuk mempertahankan diri, namun, di-
dasarkan pada pertarungan untuk me-
naklukkan dan diawasi dengan kekuatan. Ia
tidak bisa menghitung lagi sudah berapa
banyak nyawa melayang di tangannya mau
pun yang dieksekusi atas perintahnya. Tiga
Negara dalam keadaan damai saat ini:
pembantaian selama perang bertahun-tahun
sudah menjadi sejarah. Takeo dan Kaede
turun tangan untuk mengurus semua karena
kekerasan diperlukan untuk pertahanan atau
hukuman bagi pelaku tindakan kriminal:
mereka mengawasi ketat para ksatria dan
memberi jalan keluar bagi ambisi dan agresi.
Serta banyak ksatria yang mengikuti bim-
bingan Makoto, menyingkirkan panah dan
pedang, bersumpah tidak akan membunuh
lagi.
Kelak aku akan melakukan hal yang sama,
pikir Takeo. Tapi bukan sekarang. Belum
saatnya.
Dialihkan lagi perhatiannya pada per-
temuan, mengamati Zenko, Hana dan ber-
sama anak-anak mereka, dan ia bersumpah
dalam hati untuk memecahkan semua per-
soalan tanpa pertumpahan darah.*
Rasa sakitnya kembali terasa saat pagi hari,
hingga memaksa Takeo terbangun. Dipang-
gilnya pelayan agar membawakan teh,
kehangatan sesaat dan mangkuk meredakan
nyeri di tangan cacatnya. Hari masih hujan,
udara di dalam kediaman terasa menyesakkan
napas dan lembap. Mustahil untuk bisa
tidur. Diperintahkannya pelayan untuk
membangunkan jurutulisnya dan petugas
agar membawa lentera. Sewaktu orang-orang
tersebut sudah datang, ia duduk di luar di
beranda bersama mereka lalu memeriksa
catatan-catatan Shirakawa dan Fujiwara,
membicarakan rincian serta mempertanyakan
ketidaksesuaian sampai langit mulai berwarna
pucat dan terdengar kicau burung dari
taman. Takeo memiliki ingatan yang baik,
visualisasi dan daya tangkap yang kuat;
semua itu berkat latihan selama bertahun-
tahun. Sejak bertarung melawan Kotaro, saat
kehilangan kedua jari di tangan kanannya. ia
mendiktekan banyak hal pada juru tulisnya,
dan ini juga menambah kekuatan ingatan.
Dan seperti ayah angkatnya, Shigeru. ia
menjadi sangat menyukai serta menghargai
catatan: bagaimana segalanya bisa dicatat
serta diingat; bagaimana catatan bisa men-
dukung dan memperbaiki ingatan.
Pemuda istimewa ini mendampinginya
hampir sepanjang waktu akhir-akhir ini;
salah satu dari banyak anak laki-Iaki yang
menjadi yatim piatu karena bencana gempa
bumi di usia sepuluh tahun, dia menemu-
kan tempat berlindung di Terayama dan
dididik di sana; kecerdasan dan kemamp-
uannya yang cepat dengan kuas sudah diakui,
begitu pula dengan kerajinannyaia
merupakan salah satu dari orang-orang yang
belajar dengan hanya ditemani cahaya
kunang-kunang dan pantulan salju, begitu
kata pepatahdan akhirnya dia dipilih
Makoto untuk bergabung dalam lingkungan
rumah tangga Lord Otori di Hagi.
Bersifat pendiam, dan tidak peduli dengan
sake, kepribadiannya agak membosankan bila
ditilik dari penampilannya, namun memiliki
komentar tajam bernada sarkasme saat hanya
berdua dengan Takeo, tidak terkesan oleh
siapa pun atau apa pun, memperlakukan
semua orang dengan rasa hormat, me-
merhatikan semua kekurangan dan kelebihan
dengan jernih dan sikap welas asih tanpa
prasangka. Namanya Minoru, yang membuat
Takeo senang karena ia sendiri pernah mem-
bawa nama itu dalam jangka waktu yang
begitu pendek hingga terasa seperti
kehidupannya yang lain.
Ia menulis dengan cepat dan indah.
Kedua tanah warisan itu rusak parah
akibat gempa, rumah-rumah yang besar dan
indah di pedesaan luluh lantak terbakar api.
Shirakawa telah dibangun kembali dan adik
iparnya yang satu lagi, Ai, secara teratur
mengunjunginya dalam satu tahun bersama
putri-putrinya. Suaminya, Sonoda Mitsuru
sesekali mendampingi, namun tugas sering-
kali menahannya di Inuyama. Ai adalah
orang yang praktis dan pekerja keras serta
memanfaatkan contoh yang telah dibuat
kakaknya. Shirakawa telah pulih dari
pengelolaan yang salah serta diabaikan oleh
ayah mereka dan semakin berkembang,
memberi keuntungan besar dalam bentuk
beras, mulberi, persimmon, sutra serta kertas.
Tanah kekayaan milik Fujiwara selama ini
diatur oleh Shirakawa; pada dasarnya lebih
kaya dan kini pun menunjukkan keuntungan
yang mencukupi. Takeo agak enggan untuk
mengembalikannya ke tangan putra Fuji-
wara, bahkan kalau pun dia merupakan
pemilik yang sah. Seperti saat ini,
keuntungan bekas wilayah Fujiwara ini
meyumbang pada perekonomian Tiga
Negara. Ia curiga Kono ingin mengambil
sebanyak mungkin, memeras sumber daya
yang ada sebanyak-banyaknya, talu meng-
habiskan hasilnya di ibukota.
Ketika hari sudah terang, Takeo mandi.
kemudian tukang cukur mencabut dan
merapikan rambut dan janggutnya. Makan
sedikit nasi dan sup kemudian mengenakan
pakaian resmi untuk pertemuan dengan
putra Fujiwara, menemukan sedikit
kenyamanan pada kelembutan kain sutra
serta motif yang tidak mengumbar ke-
anggunan: bunga belukar wisteria berwarna
ungu muda di atas latar berwarna ungu tua
pada jubah bagian dalam dan tenunan yang
lebih abstrak pada bagian luarnya.
Pelayan menempatkan sebuah topi hitam
kecil di atas kepalanya, dan Takeo meng-
ambil pedangnya, Jato, dari rak ukiran yang
sangat indah tempat pedang itu berada
sepanjang malam lalu menggantungkan di
sabuknya, seraya memikirkan segala macam
bentuk sarung pembungkus yang pernah
dilihatnya, mulai dari kulit ikan hiu hitam
lusuh yang membungkus pegangannya
ketika, di tangan Shigeru telah menyelamat-
kan hidupnya. Kini baik pegangan maupun
sarungnya dihiasi dengan dekorasi yang
indah dan Jato sudah tidak pernah lagi
merasakan darah selama bertahun-tahun. Ia
ingin tahu apakah akan mengeluarkan
pedang itu dari sarungnya lagi dalam per-
tempuran, dan bagaimana ia bisa meng-
gunakan pedang itu dengan tangan kanannya
yang sudah tidak utuh.
Takeo berjalan melintasi taman dari sayap
timur menuju aula utama rumah besar dan
indah itu. Hujan telah reda namun taman
masih basah dan bunga wisteria bergelayut
berat dengan sisa titik air hujan, aromanya
berbaur dengan aroma rumput basah, aroma
garam dari pelabuhan dan segala macam
bebauan dari kota. Di balik dinding bisa
didengamya debak-debuk bunyi daun jendela
ketika kota terbangun, dan dari kejauhan
terdengar teriakan pedagang jalanan di pagi
hari.
Para pelayan melangkah tanpa suara di
depannya, membuka pintu, pijakan lembut
kaki mereka di lantai yang mengkilap.
Minoru, yang tidak selesai sarapan, ber-
gabung dengannya tanpa suara, mem-
bungkuk hormat kemudian berjalan be-
berapa langkah mengikuti di belakangnya.
Seorang pelayan berjalan di sampingnya
membawa meja tulis, kertas, kuas, batu tinta
dan air.
Zenko sudah di aula utama, berpakaian
resmi seperti Takeo namun lebih mewah lagi,
benang emas berkilauan di bagian kerah dan
sabuknya. Takeo mengangguk ke arahnya,
menyambut penghormatannya, lalu menye-
rahkan Jato ke tangan Minoru, yang
kemudian menempatkan pedang itu dengan
hati-hati di sebuah rak indah yang ada di
sebelah samping. Pedang Zenko sudah
ditempatkan di rak yang sama. Takeo lalu
duduk di ujung ruangan, melayangkan
pandangan ke sekeliling ruangan, melihat
dekorasi, kertas kasa, ingin tahu bagaimana
anggapan Kono tentang semua yang ada di
sini setelah melihat istana Kaisar. Kediaman
itu tidak sebesar maupun semegah seperti di
Hagi atau Inuyama, dan ia menyesal karena
tidak menerima kedatangan tamu bangsa-
wannya di sana. Dia akan mendapat kesan
yang salah mengenai kami: dia akan mengira
kami tidak sopan dan sederhana. Apakah
memang lebih baik dia berpikir seperti itu?
Zenko berbicara tentang malam sebelum-
nya. Takeo mengungkapkan persetujuannya
dan memuji mereka. Minoru menyiapkan
tinta di atas meja tulis kecil lalu duduk
dengan tumit, pandangan mata menunduk
seolah sedang bermeditasi. Hujan turun
perlahan.
Tak lama kemudian mereka mendengar
suara yang menyerukan ada tamu yang
datang, anjing menyalak dan derap kaki berat
pengangkat tandu. Zenko bangkit lalu
berjalan ke beranda. Takeo mendengarnya
memberi salam pada tamu mereka, kemudian
Kono melangkah masuk ke dalam ruangan.
Keadaan menjadi agak canggung selama
beberapa saat ketika tak satu pun dari mereka
merasa harus membungkuk memberi hormat
lebih dulu; alis mata Kono bergerak cepat
naik lalu membungkuk hormat, tapi dengan
sikap santun santun yang dibuat-buat hingga
menghilangkan tanda penghormatan. Takeo
menunggu lama satu helaan napas, kemudian
membalas salam.
"Lord Kono," sapanya dengan tenang.
"Suatu kehormatan bagiku Anda bisa ber-
kunjung kemari."
Sewaktu Kono duduk tegak, Takeo meng-
amati wajahnya. Ia belum pernah bertemu
dengan ayah bangsawan ini, tapi itu tidak
mencegah Fujiwara untuk datang meng-
hantui mimpi-mimpinya. Kini ia tengah
memberi muka pada putra dari musuh
lamanya, yang berdahi lebar, bentuk mulut
berlekuk, tanpa mengetahui bahwa Kono
memang mirip ayahnya dalam beberapa hal,
meskipun tidak mirip sekali.
"Justru kehormatan bagiku bisa bertemu
Lord Otori," sahut Kono, dan walaupun
kata-kata itu sopan, Takeo tahu bukan itu
maksudnya. Dan hanya ada sedikit peluang
untuk perbincangan yang jujur. Pertemuan
itu akan alot dan tegang, dan ia haras
bersikap cerdik, kelihatan mahir serta penuh
semangat. Takeo berusaha menenangkan
diri, melawan kelelahan juga rasa sakit.
Mereka mulai membicarakan tentang
harta kekayaan, Zenko menjelaskan apa yang
dia ketahui. Kono mengungkapkan
keinginan untuk melihatnya sendiri, dan
langsung dipenuhi Takeo tanpa protes karena
merasa kalau Kono sebenarnya tidak terlalu
tertarik pada wilayah itu dan tak bermaksud
tinggal di sana; kalau dia mungkin hanya
ingin diakui sebagai pemilik wilayah itu;
kalau dia hanya ingin dikirimi sejumlah
keuntungantidak seluruh pajak tapi
sebagian saja. Harta kekayaan itu hanyalah
alasan dari kunjungan Kono: alasan
sempurna yang masuk akal. Kono datang
dengan tujuan lain, tapi dia terus membahas
tentang hasil bumi sehingga Takeo mulai
bertanya-tanya kapan dia akan mengatakan
tujuannya yang sebenarnya. Tak lama setelah
itu, seorang penjaga datang membawa pesan
untuk Lord Arai. Zenko meminta maaf
dengan berlebihan lalu berkata kalau dia
terpaksa pergi tapi akan bergabung lagi saat
makan siang.
Kepergiannya meninggalkan mereka ber-
dua dalam kesenyapan. Minoru meletakkan
kuasnya, semua pembicaraan telah ditulisnya.
Kono berkata, "Aku harus membicarakan
satu hal yang memerlukan penanganan yang
bijaksana. Sebaiknya memang dibicarakan
berdua saja dengan Lord Otori."
Takeo menaikkan alis lalu menjawab,
"Juru tulisku tetap di sini." Ia memberi
isyarat pada sisa pengawal yang lain untuk
meninggalkan ruangan.
Setelah semua orang pergi, Kono diam
selama beberapa saat. Ketika bicara, nada
suaranya lebih hangat dan sikapnya lebih
alami, tidak terlalu dibuat-buat.
"Aku ingin Lord Otori tahu bahwa aku
hanyalah seorang utusan. Aku tidak
memendam kebencian terhadap Anda. Aku
tahu sedikit sejarah dari kedua keluarga
kitakeadaan yang tidak sepantasnya terjadi
pada Lady Shirakawanamun tindakan
ayahku acapkali membuat ibuku dan aku
tertekan, ketika beliau masih hidup. Aku
tidak percaya kalau ayahku tidak bersalah."
Tidak bersalah? pikir Takeo. Semua
kesalahan justru ada padanya: penderitaan dan
rusaknya wajah istriku, terbunuhnya Amano
Tenzo, pembantaian tanpa perasaan pada
kuda pertamaku, Raku, serta semua yang
kehilangan nyawa di pertempuran Kusahara
dan pada saat menarik mundur. Ia tidak
bicara sepatah kata pun.
Kono meneruskan, "Ketenaran Lord Otori
telah menyebar ke seluruh Delapan Pulau.
Kaisar pun sudah mendengarnya. Paduka
Yang Mulia beserta kalangan Istananya
mengagumi cara Anda mewujudkan
kedamaian di Tiga Negara."
"Aku merasa tersanjung."
"Sayangnya semua prestasi hebat itu tidak
mendapat persetujuan Kaisar." Kono ter-
senyum dengan keramahan dan pengertian
yang tidak tulus. "Dan prestasi Anda berasal
dari kematianaku tak ingin mengatakan
itu sebagai pembunuhanperwakilan di
Tiga Negara yang diakui Kaisar, Arai
Daiichi."
"Lord Arai tewas, seperti ayahmu, dalam
gempa."
"Aku rasa Lord Arai ditembak oleh salah
satu pengikut Anda, perompak Terada
Fumio, yang pada dasarnya sudah penjahat.
Gempa itu merupakan hukuman dari Surga
sebagai akibat dari tindak pengkhianatan
melawan wakil kaisar: itu yang dipercaya di
ibukota. Ada juga kematian yang tak dapat
dijelaskan, berhubungan dengan Kaisar yang
berkuasa saat itu: kematian Lord Shirakawa,
misalnya, kemungkinan di tangan Kondo
Koichi, yang saat itu bekerja pada Anda, dan
yang juga terlibat dalam kematian ayahku."
Takeo membalas, "Kondo sudah
meninggal bertahun-tahun lalu. Semua ini
sudah menjadi masa lalu. Di Tiga Negara
dipercaya bahwa Surga turun tangan untuk
menghukum saudara-saudara dari kakekku
dan Arai atas tindakan dan pengkhianatan
keji mereka. Arai menyerang pasukanku yang
tidak bersenjata. Bila ada yang disebut peng-
khianatan, maka dialah yang berkhianat."
Bumi menghantarkan apa yang diinginkan
Surga.
"Nah, putranya, Lord Zenko, adalah
saksinya dan laki-laki dengan kejujuran
pastilah berkata yang sebenarnya," sahut
Kono acuh tak acuh. Tugasku yang tidak
menyenangkan adalah memberitahukan
bahwa karena Anda tidak pernah meminta
ijin atau dukungan dari Kaisar, tidak pernah
mengirim pajak atau upeti ke ibukota, maka
pemerintahan Anda dianggap tidak sah dan
Anda diminta untuk turun takhta. Anda
akan diampuni bila mengasingkan diri ke
pulau terpencil. Pedang keturunan leluhur
Otori harus dikembalikan kepada Kaisar."
"Aku sungguh tidak mengerti Anda berani
membawa pesan semacam ini," sahut Takeo,
seraya menyembunyikan rasa kaget dan
marahnya. "Di bawah kekuasaankulah Tiga
Negara menjadi damai dan sejahtera. Aku tak
berniat turun takhta sampai putriku cukup
dewasa untuk menjadi pewarisku. Aku ingin
membuat perjanjian dengan Kaisar, dan
orang lain yang ingin mendekatiku dengan
damai; aku memiliki tiga putri yang bisa
kuaturkan pernikahan politis bagi mereka.
Namun aku takkan terintimidasi oleh
ancaman."
"Tidak seorang pun berani mengancam
Anda," gumam Kono, sulit membaca
ekspresi wajahnya.
Takeo bertanya, "Mengapa baru sekarang
kau datang? Di mana minat Kaisar bertahun-
tahun lalu, ketika Iida Sadamu menjarah
Tiga Negara dan membunuhi rakyatnya?
Apakah Iida bertindak atas persetujuan
Kaisar?"
Dilihatnya Minoru agak menggerakkan
kepala, dan berusaha mengendalikan ke-
gusarannya. Tentu saja Kono memang ber-
harap untuk membuatnya gusar, berharap
menggiringnya membuat pernyataan terbuka
tentang sikap membangkang yang akan
diartikan sebagai pemberontakan selanjutnya.
Zenko dan Hana ada di balik semua ini,
pikirnya. Tapi pasti ada alasan lain mengapa
merekadan Kaisarberani bergerak
menentang dirinya saat ini Kelemahan macam
apa yang sedang mereka eksploitasi? Kekuatan
tambahan apa yang mereka kira mereka
punya?
"Aku tak bermaksud untuk tidak meng-
hormati Kaisar," ujar Takeo dengan hati-
hati. "Namun beliau dihormati di seluruh
penjuru Delapan Pulau atas tujuannya untuk
mewujudkan kedamaian. Tentu saja beliau
takkan berperang melawan rakyatnya sendiri,
kan?"
Benarkah Kaisar takkan menggalang
kekuatan untuk melawanku?
"Lord Otori belum mendengar kabar ter-
baru," tutur Kono dengan nada sedih.
"Kaisar telah menunjuk jenderal baru:
keturunan salah satu keluarga tertua di
wilayah Timur, pemimpin sepuluh ribu
pasukan. Lebih dari segalanya, Kaisar ber-
tujuan damai, namun beliau tidak dapat
mengampuni tindakan kriminal, dan kini
beliau memiliki tangan kanan yang kuat
untuk menegakkan hukum dan keadilan."
Kata-kata yang dilontarkan dengan lembut
itu mengandung sengatan penghinaan, dan
Takeo merasakan gelombang panas dalam
dirinya. Hampir tak tertahankan karena ia
dianggap penjahat: darah Otori dalam
dirinya berontak menentang anggapan
tersebut. Namun selama bertahun-tahun ia
telah memadamkan tantangan dan per-
selisihan melalui perundingan dan diplomasi
yang cerdas. Ia tidak percaya kalau cara ini
akan mengecewakannya sekarang. Dibiarkan-
nya hinaan itu menyirami dirinya sambil
berusaha mengendalikan diri, dan mulai
mempertimbangkan jawaban seperti apa
yang akan ia berikan.
Jadi mereka mempunyai jenderal perang.
Mengapa aku tak pernah mendengar namanya?
Di mana Taku saat aku membutuhkannya? Di
mana Kenji?
Kelebihan senjata serta pasukan yang
disiapkan Arai Zenko: mungkinkah mereka
mendukung ancaman baru ini? Senjata-
senjata: bagaimana kalau itu ternyata senjata
api? Bagaimana jika mereka dalam perjalanan
ke Timur?
"Anda di sini sebagai tamu dari penguasa
yang berada di bawah kekuasaanku, Arai
Zenko," akhirnya ia berkata. "itu berarti
tamuku juga. Kurasa Anda harus memper-
panjang masa tinggal Anda di wilayah Barat,
mengunjungi kekayaan mendiang ayah
Anda, lalu kembali bersama Lord Arai ke
Kumamoto. Aku akan memanggil Anda
sewaktu sudah kuputuskan bagaimana men-
jawab ke Kaisar, ke mana aku akan pergi jika
ingin mengundurkan diri, dan bagaimana
cara terbaik untuk mempertahankan
kedamaian."
"Kuulangi lagi, aku hanyalah utusan,"
sahut Kono, lalu membungkuk dengan
ketulusan yang jelas.
Zenko kembali dan makan siang sudah
siap: meskipun hidangannya mewah dan
lezat, Takeo nyaris tidak bisa merasakannya.
Perbincangan berjalan dengan ringan dan
sopan; ia mencoba turut ambil bagian di
dalamnya.
Saat mereka selesai makan, Kono dikawal
oleh Zenko menuju ke wisma tamu. Jun dan
Shin sudah menunggu di luar di beranda.
Mereka bangkit dan mengikuti Takeo tanpa
suara ketika ia kembali ke kamarnya.
"Lord Kono tidak boleh meninggalkan
kediaman ini," katanya pada mereka, "Jun,
tempatkan penjaga di gerbang. Shin, segera
ambil alih perintah di pelabuhan. Lord Kono
akan tinggal di wilayah Barat sampai kuberi-
kan ijin tertulis baginya untuk kembali ke
Miyako. Hal yang sama berlaku juga untuk
Lady Arai dan kedua putranya."
Kedua saudara sepupu itu bertukar
pandang tapi tidak berkomentar selain,
"Tentu saja, Lord Otori."
"Minoru," ujar Takeo pada juru tulisnya.
"Pergilah dengan Shin ke pelabuhan dan cari
tahu rincian tentang kapal-kapal yang sedang
merapat, terutama yang menuju ke Akashi."
"Aku mengerti," sahut Minoru. "Aku akan
kembali secepatnya."
Takeo bersantai di beranda lalu men-
dengarkan suasana di kediaman berubah
ketika semua instruksinya dilaksanakan:
langkah kaki penjaga, perintah Jun yang
keras serta dengan paksaan, para pelayan
yang bingung berjalan bergegas dan
komentar bisik-bisik, satu seruan terkejut
dari Zenko, saran Hana yang diucapkan
dengan bergumam. Ketika Jun kembali,
Takeo menyuruhnya untuk tetap berada di
luar kamar dan jangan sampai ada orang
yang mengganggunya. Kemudian ia istirahat
di dalamnya, lalu membolak-balik catatan
Minoru tentang pertemuan dengan Kono
selagi menunggu juru tulisnya kembali.
Huruf-huruf dalam tulisan seakan
melompat ke arahnya dari halaman catatan,
kaku dan goresan dalam tulisan tangan
Minoru yang nyaris sempurna. Pengasingan,
penjahat, pengkhianatan.
Takeo berjuang untuk mengendalikan
amarahnya yang timbul akibat penghinaan
semacam ini, sadar kalau Jun hanya berada
tiga langkah darinya. Hanya tinggal me-
ngeluarkan satu perintah lagi, dan mereka
semua akan mati: Kono, Zenko, Hana dan
anak-anaknya... darah mereka akan menyapu
rasa malu yang bisa dirasakan menoreh
lulangnya, mengikis organ-organ tubuhnya.
Lalu ia akan menyerang Kaisar serta
jenderalnya sebelum musim panas berakhir,
mendesak mereka kembali ke Miyako, mem-
porakporandakan ibukota. Hanya dengan
cara inilah kemarahannya bisa reda.
Dipejamkan matanya, melihat motif
gambar di kertas kasa terukir di kelopak
matanya, lalu menghela napas panjang,
mengenang bangsawan lain yang telah mem-
bunuh untuk menyapu habis penghinaan
dan akhimya mencabut nyawa orang lain
demi kesenangannya sendiri, membayangkan
betapa mudahnya mengambil jalan keluar
seperti itu dan menjadi seperti Iida Sadamu.
Dengan penuh kesadaran, disingkir-
kannya rasa terhina dan tikaman rasa malu
jauh-jauh, seraya berkata pada dirinya sendiri
kalau pemerintahannya memang ditakdir-
kan dan direstui Surga: ia melihat restu ini
dengan kehadiran burung houou, dengan
kebahagiaan rakyatnya. Pada akhirnya
kembali lagi pada keputusan untuk meng-
hindari pertumpahan darah dan perang
sebisa mungkin, dan tidak akan melakukan
apa pun tanpa berkonsultasi dengan Kaede
dan penasihat lainnya.
Keputusan ini segera saja diuji kebenaran-
nya, ketika Minoru kembali dari ruang
catatan petugas pelabuhan.
"Kecurigaan Lord Otori benar," tuturnya.
"Dibuat seolah-olah satu kapal berangkat ke
Akashi saat laut pasang semalam, tapi
sertifikat pemeriksaan muatannya belum
diisi. Shin membujuk kepala pelabuhan
untuk segera menyelidikinya."
Takeo memicingkan mata tanpa ber-
komentar.
"Lord Otori jangan khawatir," ujar
Minoru untuk meyakinkan. "Shin hampir
tidak perlu bertindak kasar. Orang-orang
yang bertanggung jawab sudah dikenali;
pegawai pabean yang mengijinkan kapalnya
berangkat, dan pedagang yang menangani
muatan. Mereka sudah ditahan, menunggu
keputusan Anda tentang kelanjutan nasib
mereka." Ia merendahkan suara. "Tak satu
pun dari mereka mengakui dari mana asal
muatan tersebut."
"Kita harus mencurigai yang terburuk,"
sahut Takeo. "Mengapa pula harus meng-
hindari prosedur pemeriksaan? Tapi jangan
bicarakan hal ini secara terang-terangan. Kita
harus berusaha menangani mereka sebelum
sampai di Akashi."
Minoru tersenyum tipis. "Aku juga ada
kabar baik untuk Anda. Kapal Terada Fumio
sedang menunggu di galangan. Mereka akan
tiba di Hofu saat laut pasang malam ini."
"Dia datang di saat yang tepat," seru
Takeo, semangatnya segera bangkit. Fumio
dan ayahnya adalah teman lamanya yang
mengawasi pasukan kapal yang digunakan
Klan Otori untuk melakukan perdagangan
dan mempertahankan garis pantai mereka.
Fumio pergi selama berbulan-bulan bersama
tabib Ishida, dalam perjalanan yang sering
dilakukan untuk perdagangan dan pen-
jelajahan.
"Katakan pada Shin untuk membawa
pesan pada Fumio kalau dia akan ke-
datangan tamu malam ini. Pesannya tak
perlu terlalu jelas. Fumio pasti mengerti."
Takeo sangat lega untuk beberapa hal.
Fumio pasti punya berita terbaru mengenai
Kaisar; jika ia bisa segera berangkat, maka
peluang untuk mengejar kapal ilegal itu
cukup besar; dan Ishida pasti membawa
obat-obatan, sesuatu yang bisa meredakan
rasa sakitnya yang berkepanjangan.
"Dan sekarang aku harus bicara dengan
adik iparku. Panggil Lord Zenko untuk
datang menghadap."
Ia senang punya alasan tentang petugas
pabean untuk menekan adik iparnya. Zenko
mengungkapkan permintaan maaf dan ber-
janji untuk mengatur eksekusinya, me-
yakinkan Takeo kalau itu adalah peristiwa
yang jarang terjadi, hanya contoh dari
keserakahan manusia.
"Kuharap kau benar," sahut Takeo. "Aku
ingin kau meyakinkan kesetiaan penuhmu
kepadaku: kau berhutang nyawa padaku; kau
menikah dengan adik istriku; ibumu adalah
sepupuku dan sahabatku. Kau memegang
Kumamoto atas keinginan dan ijinku.
Kemarin kau menawarkan salah satu
putramu kepadaku. Kuterima tawaranmu.
Tentu saja aku akan membawa keduanya;
saat berangkat ke Hagi mereka akan
menemaniku. Mulai saat ini mereka akan
tinggal bersama keluargaku dan dibesarkan
sebagai putraku. Aku akan mengangkat
Sunaomi, bila kau tetap setia padaku. Hidup
Sunaomi dan adiknya akan diserahkan ke
tanganku bila ada sedikit saja tanda
ketidaksetiaan. Masalah pernikahan akan
diputuskan nanti. Istrimu boleh bergabung
dengan kedua putranya di Hagi, jika dia
mau, tapi aku yakin kau menginginkan
istrimu tetap bersamamu."
Takeo mengamati wajah adik iparnya
lekat-lekat ia bicara. Zenko tidak berani
menatapnya. Bola matanya ikit berputar dan
bicara terlalu cepat untuk memberi
tanggapan.
"Lord Takeo harus tahu kalau aku betul-
betul setia. Apa yang telah Kono katakan
hingga Anda beranggapan seperti ini? Apakah
dia bicara tentang masalah-masalah di
wilayah Timur?"
Jangan pura-pura tidak tahu! Takeo
tergoda ingin langsung menantangnya, tapi
memutuskan kalau saatnya belum tiba.
"Kita abaikan saja apa yang telah
dikatakannya: itu tidak penting. Sekarang, di
hadapan semua saksi di sini, ucapkan
sumpah setiamu kepadaku."
Zenko melakukannya dengan mem-
bungkuk dalam-dalam, tapi Takeo ingat
bagaimana ayahnya, Arai Daiichi, telah
bersumpah setia hanya untuk meng-
khianatinya, dan di saat yang paling genting
lebih memilih kekuasaan melebihi dari
nyawa kedua putranya.
Putranya pun akan bersikap sama, pikirnya.
Seharusnya kuperintahkan dia mencabut
nyawanya sekarang juga. Namun tak kuasa
bertindak seperti itu, karena pada akhirnya
semua kesedihan hanya akan menimpa
keluarganya sendiri. Lebih baik tetap mencoba
menjinakkannya, ketimbang membunuhnya.
Tapi betapa lebih mudahnya kalau dia mati.
Disingkirkannya pikiran itu seraya berjanji
pada dirinya sendiri sekali lagi untuk ber-
pegang pada jalan yang lebih rumit dan sulit,
jauh dari kemudahan yang menipu dari
pembunuhan atau bunuh diri. Begitu Zenko
selesai menyampaikan semua keberatannya,
semua dicatat oleh Minoru, Takeo ber-
istirahat di wismanya, berkata kalau ia akan
makan sendirian dan istirahat lebih awal
karena hendak berangkat ke Hagi keesokan
paginya. Ia ingin sekali berada di rumah,
berbaring bersama istrinya dan membuka
hati kepadanya, bertemu dengan putri-
putrinya. Dikatakannya pada Zenko agar
kedua putranya harus siap melakukan
perjalanan bersamanya.
Sepanjang hari hujan turun dan reda. tapi
saat ini langit mulai cerah, angin berhembus
lembut dari selatan meluluhkan awan gelap.
Matahari tenggelam dalam warna merah
muda dan cahaya keemasan yang membuat
banyak warna hijau di taman bermandikan
cahaya. Keadaan akan baik-baik saja pada
pagi hari, hari yang baik untuk melakukan
perjalanan, baik juga untuk kegiatan malam
hari yang terlintas di benaknya.
Takeo mandi lalu mengenakan jubah dari
bahan katun tipis seolah bersiap pergi tidur,
makan sedikit tapi tanpa minum sake,
kemudian menyuruh semua pelayan pergi,
mengatakan pada mereka kalau ia tak mau
diganggu. Kemudian menenangkan dirinya
sendiri, bersila di matras dengan mata ter-
pejam dan kedua jari telunjuk dan ibu jari
saling bersentuhan ditekan seakan tenggelam
dalam posisi meditasi. Dipasang telinganya
baik-baik untuk mendengarkan suara-suara
di dalam kediaman.
Tiap suara terdengar olehnya: percakapan
pelan para penjaga di gerbang, pelayan dapur
mengobrol sambil membersihkan piring lalu
menyimpannya, anjing-anjing menyalak,
musik dan tempat minum-minum di sekitar
pelabuhan, gemuruh tanpa henti air laut,
gemerisik dedaunan dan teriakan burung
hantu dari gunung.
Terdengar olehnya Zenko dan Hana
membicarakan pengaturan untuk keesokan
harinya, tapi percakapan yang sepele, seolah
mereka ingat kalau ia mungkin saja sedang
mendengarkan. Dalam permainan berbahaya
yang telah mereka mulai, mereka tidak mau
ambil resiko Takeo mencuri dengar strategi
mereka, terutama bila ia memang jadi
menahan kedua putra mereka. Tak lama
kemudian, mereka bertemu Kono untuk
makan malam, namun mereka sama berhati-
hatinya: yang terdengar tak lebih dari tata
rambut model terbaru dan cara berpakaian di
istana, kegemaran Kono akan puisi dan
drama, serta olahraga para bangsawan, bola
tendang dan berburu anjing.
Percakapan itu menjadi semakin hidup:
seperti ayahnya, Zenko gemar minum sake.
Takeo berdiri dan mengganti pakaiannya,
memakai jubah yang tidak mencolok
berwarna pudar seperti yang biasa dikenakan
pedagang. Ketika melewati Jun dan Shin,
yang sedari tadi duduk di luar pintu, Jun
menaikkan alis; Takeo menggelengkan
kepala. Tak ingin ada yang tahu kalau ia
pergi. Dipakainya sandal jerami di anak
tangga taman, menghilang lalu berjalan lewat
gerbang yang masih terbuka. Anjing-anjing
menggiringnya dengan tatapan mata tapi
para penjaga tidak memerhatikannya.
Bersyukurlah kalian tak berjaga di gerbang
istana di Miyako, katanya tanpa suara pada
anjing-anjing. Karena mereka akan memburu
kalian dengan hujan anak panah untuk
olahraga.
Di satu sudut yang gelap tidak jauh dari
pelabuhan, Takeo melangkah masuk ke
bayangan tak tertihat dan keluar dengan
penyamarannya sebagai pedagang yang
sedang terburu-buru untuk pekerjaan di
kota. Udara terasa penuh dengan aroma
garam, ikan yang sedang dikeringkan dan
rumput laut di atas rak-rak di tepi pantai,
ikan dan gurita panggang di rumah makan.
Lentera menerangi jalanan sempit dan cahaya
lampu bersinar jingga dari balik kertas kasa.
Di tepi galangan, kapal-kapal kayu saling
bergesekan, terombang-ambing oleh ombak,
air menghantam badan kapal, dengan tiang
pancang yang kekar dan berwarna gelap di
bawah siraman cahaya malam penuh
bintang. Di kejauhan dapat dilihatnya pulau-
pulau dari Laut Lingkar; di balik bentuknya
yang menyembul tajam tampak cahaya
temaram bulan yang baru naik.
Tungku bara menyala di samping tali
tambatan salah satu kapal besar, dan Takeo,
dengan menggunakan dialek kota itu, ber-
seru pada orang-orang yang, memanggang
potongan-potongan abon kering dan berbagi
sebotol sake. "Apakah Terada datang dengan
kapal ini?"
"Ya, benar," sahut satu orang. "dia sedang
makan di Umedaya."
"Apakah kau berharap melihat kirin*?"
timpal yang lain. "Lord Terada menyem-
* Kirin atau qilin (dalam bahasa cina)
merupakan mahluk dongeng yang kemun-
culannya dianggap sebagai simbol kemak-
murannegaradankearifanpenguasa
bunyikannya di tempat yang aman sampai
bisa diperlihatkan kepada penguasa kami,
Lord Otori."
"Kirin?" Takeo terkejut. Kirin adalah
hewan dalam tongeng, separuh naga, separuh
kuda, dan separuh singa. Dikiranya hewan
itu hanya legenda. Apa yang ditemukan
Terada dan Ishida di daratan utama?
"Seharusnya ini rahasia," orang pertama
memperingatkan temannya. "Dan kau terus
saja mengoceh pada semua orang!"
"Tapi ini kirin!" sahut yang lainnya.
"Sungguh suatu mukjizat bisa memiliki
hewan ini hidup-hidup! Dan tidakkah itu
membuktikan bahwa Lord Otori adil dan
bijaksana melebihi yang lainnya? Pertama
burung houou, burung suci kembali ke Tiga
Negara, dan kini muncul seekor kirin!"
Orang itu menenggak lagi sakenya lalu
menawarkan botolnya pada Takeo.
"Bersulang untuk kirin dan Lord Otori!"
"Baiklah, terima kasih," sahut Takeo sambil
tersenyum. "Aku berharap bisa melihatnya
suatu hari nanti."
"Tidak akan sebelum Lord Otori melihat-
nya!" Takeo masih tersenyum selagi berjalan
menjauh, kerasnya rasa sake membangkitkan
semangatnya sama banyaknya dengan niat
baik orang-orang tadi.
Saat kudengar tidak lain dari kritikan
tentang Lord Otorisaat itulah aku akan
mengundurkan diri, katanya pada diri sendiri.
Tapi tidak sebelum saat itu tiba, walau
dipaksa sepuluh kaisar dan jenderal-
jenderalnya sekalipun.*
Umedaya adalah sebuah rumah makan yang
berada di antara pelabuhan dan distrik utama
kota, satu dari banyak bangunan rendah yang
menghadap ke arah sungai dan diapit pohon-
pohon willow. Lentera digantung di tiang-
tiang beranda dan di perahu-perahu besar
pengangkut yang ditambatkan di depannya
dengan muatan berbal-bal beras dan
gandum, serta hasil pertanian lainnya dari
pedalaman ke laut. Banyak pelanggan duduk
di luar menikmati indahnya bulan yang kini
berada di atas puncak pegunungan, meman-
tulkan warna keperakan pada alur gelom-
bang.
"Selamat datang! Selamat datang!" seru
pelayan saat Takeo menyibak tirai rumah
makan itu lalu melangkah masuk; disebut-
nya nama Terada dan dia menunjuk ke sudut
beranda yang ada di bagian dalam. Fumio
tampak sedang sibuk menelan ikan rebus
dengan tergesa-gesa sambil berbicara dengan
keras. Tabib Ishida duduk bersamanya,
makan sama lahapnya, sambil mendengarkan
dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa
anak buah Fumio. beberapa di antaranya
sudah dikenal Takeo, ada bersamanya.
Berdiri tanpa dikenali dalam kegelapan,
Takeo mengamati kawan lamanya selama
beberapa waktu. Fumio tetap kelihatan kekar
seperti biasa, dengan pipi tembam dan kumis
tipis, meskipun kini kelihatan ada bekas luka
baru di salah satu pelipisnya. Ishida kelihatan
lebih tua, lebih kurus kering, kulitnya
kekuningan.
Takeo senang melihat keduanya lalu
melangkah naik ke area duduk. Salah satu
mantan perompak segera melompat berdiri
menghalangi jalannya, mengira kalau ia
hanyalah pedagang yang tak penting. Tapi
setelah beberapa saat terkejut dan ke-
bingungan, Fumio bangkit, mendorong anak
buahnya ke samping, sambil berbisik, "Ini
Lord Otori!" lalu memeluk Takeo.
"Walaupun memang sedang menunggu-
mu, aku tidak mengenalimu!" serunya.
"Misterius dan aneh: aku tidak akan ter-
biasa."
Tabib Ishida tersenyum lebar. "Lord
Otori!" Dipanggilnya pelayan untuk mem-
bawakan sake lagi. Takeo duduk di samping
Fumio, berhadapan dengan si tabib, yang
mengamatinya dengan seksama di bawah
cahaya temaram.
"Ada masalah?" tanya Ishida setelah
mereka bersulang.
"Ada beberapa hal yang perlu kubicara-
kan," sahut Takeo. Fumio memberikan
isyarat dengan kepala, lalu anak buahnya
pindah ke meja lain.
"Aku ada hadiah untukmu," katanya pada
Takeo. "Hadiah yang akan mengalihkan
perhatianmu dari masalah. Coba tebak apa
hadiahnya! Lebih hebat dari apa pun yang
pernah kau inginkan!"
"Ada satu hal yang kudambakan lebih dari
segalanya," jawab Takeo. "Yaitu melihat
seekor kirin sebelum aku mati."
"Ah. Mereka sudah mengatakannya pada-
mu. Dasar manusia brengsek yang tak ber-
guna. Akan kurobek mulut mereka."
"Mereka menceritakannya pada seorang
pedagang miskin yang tak berani," sahut
Takeo tertawa. "Aku harus mencegahmu
menghukum mereka. Lagipula, aku juga
hampir tidak percaya pada mereka. Apakah
itu benar?"
"Ya dan tidak," kata Ishida. "Tentu saja,
bukan kirin yang sesungguhnya: kirin adalah
hewan dalam dongeng, sedangkan yang ini
adalah hewan sungguhan. Tapi hewan yang
luar biasa, dan yang paling mirip dengan
kirin dibanding hewan lain yang pernah
kulihat."
"Ishida jatuh hati pada hewan itu," tutur
Fumio. "Dia menghabiskan waktu berjam-
jam menemaninya. Ia lebih parah ketim-
bang kau dan kuda tuamu itu, siapa nama-
nya?"
"Shun," sahut Takeo. Shun mati karena
usia tua tahun lalu; tak akan ada lagi kuda
sepertinya.
"Kau tidak bisa menunggangi hewan ini,
tapi mungkin bisa menggantikan Shun, agar
kau bisa mencurahkan kasih sayangmu,"
tutur Fumio.
"Aku ingin sekali melihatnya. Di mana
hewan itu sekarang?"
"Di kuil Daifukuji; mereka menemukan
taman yang tenang untuk hewan itu, dengan
dinding yang tinggi. Kami akan perlihatkan
padamu besok. Karena kau sudah merusak
kejutan kami, maka sekalian saja ceritakan
masalah-masalahmu pada kami." Fumio
menuang sake lagi.
"Apa yang kau tahu tentang jenderal baru
Kaisar?" tanya Takeo.
"Kalau kau tanya aku beberapa minggu
lalu, aku akan jawab, 'Tidak tahu apa-apa,'
karena kami sudah pergi selama enam bulan,
tapi kami pulang melalui Akashi, dan kota
itu sibuk membicarakannya. Namanya Saga
Hideki, dengan julukan Pemburu Anjing."
"Pemburu Anjing?"
"Dia sangat suka berburu anjing, dan
kabarnya mahir melakukannya. Jenderal itu
mahir berkuda dan memanah, serta ahli
siasat perang yang cerdas. Mendominasi
propinsi-propinsi di wilayah Timur, kabar-
nya memiliki ambisi menaklukkan seluruh
Delapan Pulau, dan baru-baru ini ditunjuk
Kaisar untuk bertempur atas nama Paduka
Yang Mulia serta membinasakan musuh-
musuhnya dalam rangka mencapai tujuan
itu."
"Sepertinya aku termasuk dalam daftar
musuhnya," ujar Takeo. "Putra Lord
Fujiwara, Kono, datang menghadapku hari
ini. Ternyata Kaisar memintaku meng-
undurkan diri, dan jika aku menolak, beliau
akan mengirim si Penangkap Anjing untuk
melawanku."
Wajah Ishida berubah pucat ketika nama
Fujiwara disebut. "masalah," gumamnya.
"Apakah ada indikasi kalau senjata api di
perdagangkan di Imai?"
"Tidak, justru sebaliknya; beberapa
pedagang mendekatiku, menanyakan ten-
tang senjata dan bubuk mesiu, berharap
menghindar pelarangan dari Otori. Mesti
kuperingatkan padamu, mereka menawar-
kan uang dalam jumlah besar. Jika jenderal
Kaisar tengah bersiap melawanmu, kemung-
kinan dia berusaha membeli senjata api: demi
uang sebesar itu, cepat atau lambat akan ada
orang yang akan menyediakan senjata api."
"Aku khawatir mereka sudah dalam per-
jalanan," ujar Takeo, dan menceritakan pada
Fumio tentang kecurigaannya pada Zenko.
"Mereka punya waktu kurang dari sehari
untuk memulainya," sahut Fumio, meneng-
gak habis minumnya lalu berdiri. "Kita bisa
hentikan mereka. Aku ingin melihat wajah-
mu saat kuperlihatkan kirin, tapi nanti Ishida
bisa menceritakannya padaku. Tahan Lord
Kono di wilayah Barat sampai aku kembali.
Sebelum mereka bisa menandingi jumlah
senjata api, mereka takkan memancingmu
dalam pertempuran. Angin bertiup dari arah
barat: kita bisa mendapat laut pasang jika
berangkat sekarang." Dipanggil anak buah-
nya, dan mereka pun berdiri, menjejalkan
sisa makanan, menenggak habis sake,
mengucapkan selamat tinggal pada pelayan
perempuan dengan perasaan enggan. Takeo
memberitahu mereka nama kapalnya.
Fumio pergi begitu cepat hingga mereka
hampir tidak sempat mengucapkan selamat
berpisah.
Takeo ditinggal bersama Ishida. "Fumio
tak berubah," katanya, terhibur dengan tin-
dakan cekatan kawannya.
"Dia masih tetap sama," sahut Ishida.
"Seperti angin topan, tidak pernah bisa
diam." Si tabib menuang sake lagi lalu
minum sampai habis. "Dia adalah teman
seperjalanan yang memberi semangat, namun
melelahkan."
Mereka berbincang-bincang tentang per-
jalanan, dan Takeo memberi kabar tentang
keluarganya yang selalu menyita perhatian
Ishida, karena dia sudah menikah dengan
Muto Shizuka selama lima belas tahun.
"Rasa sakitmu terasa lagi?" tanya si tabib.
"Kelihatan dari wajahmu."
"Ya, cuaca yang lembap memperburuknya:
kadang kurasa masih ada sisa racun yang
hingga terasa panas. Acapkali lukanya
kelihatan memerah di balik carutannya.
Membuat sekujur tubuhku sakit."
"Akan kuperiksa nanti, berdua saja," sahut
Ishida.
"Bisakah sekarang kau kembali bersama-
ku?"
"Aku punya cukup persediaan akar-akaran
dari Shin, dan obat tidur terbuat dari bunga
candu. Untung saja kuputuskan untuk mem-
bawanya," komentar Ishida seraya meng-
ambil sebuah buntalan kain dan kotak kayu
kecil. Tadinya aku bermaksud meninggal-
kannya di kapal. Kalau tidak kubawa pasti
barang-barang ini sudah setengah perjalanan
menuju Akashi dan tidak terlalu berguna
bagimu."
Nada suara Ishida kedengaran murung.
Takeo mengira dia akan melanjutkan bicara-
nya, namun setelah beberapa saat dalam
hening yang tidak mengenakkan, si tabib
tampak berhasil mengendalikan perasaannya;
dikumpulkan barang-barangnya lalu berkata
dengan riang, "Setelah itu aku harus pergi
memeriksa kirin. Aku akan menginap di
Daifukuji malam ini. Kirin sudah terbiasa
denganku, bahkan terikat dengan diriku: aku
tak ingin membuatnya gelisah."
Sedari tadi Takeo menyadari ada suara
orang berdebat dari bagian dalam rumah
makan, seorang laki-laki berbicara dengan
bahasa asing dan suara seorang perempuan
menerjemahkan. Suara perempuan itu
membuatnya tertarik karena logatnya berasal
dari wilayah Timur, meskipun perempuan
itu bicara dengan dialek setempat, dan ada
sesuatu dengan intonasi suaranya yang tidak
asing bagi Takeo.
Ketika berjalan melewati ruang bagian
dalam, Takeo mengenali si orang asing, yang
dipanggil Don Joao. Ia yakin belum pernah
bertemu dengan perempuan yang berlutut di
samping orang asing itu, namun seperti ada
sesuatu...
Selagi ia mengira-ngira siapa perempuan
itu, si orang asing melihat Ishida lalu
memanggilnya. Ishida amat disukai orang
asing itu dan menghabiskan banyak waktu
menemani mereka, saling bertukar ilmu
pengetahuan medis, informasi tentang
perawatan serta tanaman herbal, serta
membandingkan kebiasaan dan bahasa
mereka.
Don Joao pernah bertemu Takeo beberapa
kali, tapi selalu dalam suasana resmi, dan
sepertinya saat ini dia tidak bisa mengenali.
Orang asing itu gembira bertemu sang tabib
dan ingin agar dia duduk dan mengobrol,
tapi Ishida memohon pergi karena ada pasien
yang membutuhkannya. Perempuan itu,
yang mungkin berusia dua puluh lima
tahunan, melihat sekilas ke arah Takeo, yang
terus memalingkan wajah dari perempuan
itu. Dia menerjemahkan perkataan Ishida
sepertinya perempuan itu cukup fasih
berbicara bahasa asinglalu melayangkan
pandangannya ke arah Takeo lagi; kelihatan-
nya tengah mengamati Takeo dengan penuh
seksama, seakan-akan mengira kalau mung-
kin mengenal Takeo.
Perempuan itu mengangkat tangan untuk
menutup mulut, dengan pakaiannya terlipat
ke belakang dan memperlihatkan kulit
lengannya, halus dan gelap. Takeo merasa
kulit perempuan itu amat mirip dengan
kulitnya, amat mirip dengan kulit ibunya.
Keterkejutannya tak terlukiskan, hingga
tak kuasa mengendalikan diri, mengubah
dirinya menjadi seorang bocah yang
ketakutan serta tersiksa. Perempuan itu
tercekat lalu berkata, "Tomasu?"
Air mata menggenang di matanya. Tubuh
perempuan itu terguncang karena luapan
perasaan. Takeo ingat pada seorang gadis
cilik yang menangis dengan cara yang sama
karena menangisi seekor burung yang mati,
kehilangan mainan. Selama ini ia menduga
gadis cilik itu sudah tiada, tergeletak di
sebelah ibu dan kakak perempuannya yang
mati terbujur kakuperempuan itu memili-
ki ketenangan serta wajah yang lebar mirip
ibu dan kakak perempuannya, dan warna
kulit yang sama dengannya. Takeo menyebut
nama adiknya dengan keras untuk pertama
kalinya selama lebih dari enam belas tahun:
"Madaren!"
Sirna sudah semua hal yang ada dibenak-
nya: ancaman dan wilayah Timur, misi
Fumio merebut senjata api yang diselundup-
kan, Kono, bahkan rasa sakitnya, bahkan
kirin sekalipun. Ia hanya mampu meman-
dangi adik yang dikiranya sudah tiada;
hidupnya seperti meluruh lalu memudar.
Yang ada dalam ingatannya hanyalah masa
kecilnya, keluarganya.
Ishida bertanya, "Lord, Anda baik-baik
saja? Anda tidak sehat."
Takeo bicara dengan cepat pada Madaren,
"Katakan pada Don Joao aku akan
menemuinya besok. Kabari aku di
Daifukuji."
"Aku akan datang ke sana besok,"
sahutnya, dengan tatapan terpaku pada wajah
Takeo.
Ia berhasil mcngendalikan diri lalu ber-
kata, "Kita tidak bisa bicara sekarang. Aku
akan datang ke Daifukuji; tunggu aku di
sana."
"Semoga Dia memberkati dan melin-
dungimu," ujarnya, memanjatkan doa kaum
Hidden saat berpisah. Meskipun atas perin-
tahnya kaum Hidden kini bebas untuk ber-
ibadah secara terbuka, tetap saja membuat-
nya terkejut melihat terungkapnya sesuatu
yang sebelumnya merupakan rahasia, sama
seperti salib yang dikenakan Don Joao di
dadanya tampak seperti pameran sesuatu
yang keji.
"Kau lebih tidak sehat dari yang kukira,"
seru Ishida saat mereka berdua berada di luar.
"Perlu kupanggilkan tandu?"
"Tidak, tentu saja tidak perlu!" Takeo
mengambil napas dalam-dalam. Tadi hanya
udara yang terasa pengap. Juga terlalu banyak
minum sake, terlalu cepat."
"Kelihatannya kau sangat terguncang. Kau
mengenal perempuan itu?"
"Bertahun-tahun yang silam. Aku tidak
tahu kalau dia menerjemahkan untuk orang
asing."
"Aku pernah bertemu dengannya, tapi
tidak akhir-akhir iniaku pergi selama ber-
bulan-bulan." Kota itu semakin senyap,
cahaya dimatikan satu demi satu. Selagi
mereka menyeberangi jembatan kayu di luar
Umedaya dan mengambil salah satu jalan
sempit yang mengarah ke kediaman, Ishida
berkomentar, "Perempuan itu mengenalmu
bukan sebagai Lord Otori, tapi sebagai orang
lain."
"Seperti yang tadi kubilang, aku sudah
sangat lama mengenalnya, sebelum aku
menjadi Otori."
Takeo masih setengah tercengang dengan
pertemuan tadidan cenderung setengah
menyangsikannya. Bagaimana mungkin itu
adiknya? Bagaimana dia bisa selamat dari
pembantaian yang menghabisi keluarga dan
membakar habis desanya? Tak diragukan lagi
bahwa dia bukan sekadar seorang juru
bahasa: terlihat olehnya pada tangan dan
mata Don Joao. Pria asing itu kerap mengun-
jungi rumah pelacuran itu seperti laki-laki
lain, tapi sebagian besar perempuan peng-
huninya enggan tidur dengan mereka, hanya
pelacur kelas terendah yang tidur dengan
mereka. Ia merasa ngeri saat memikirkan
hidup seperti apa yang telah dijalani adiknya.
Namun perempuan itu memanggil dengan
nama aslinya. Dan Takeo pun mengenalinya.
Di rumah terakhir sebelum sampai di
gerbang kediaman, Takeo menarik Ishida ke
bawah bayangan gelap. "Tunggu di sini
sebentar. Aku harus masuk tanpa terlihat.
Aku akan mengirim perintah pada penjaga
agar membiarkanmu masuk."
Gerbang sudah ditutup, disingsingkannya
keliman panjang jubahnya ke sabuk lalu
memanjat dinding dengan cukup ringan,
kendati hentakan saat mendarat di sisi
dinding satunya membuat sakitnya terasa
lagi. Menghilang, lalu menyelinap melewati
taman yang sunyi, melewati Jun dan Shin
menuju ke kamarnya. Mengganti pakaian
dengan jubah tidur lalu meminta dibawakan
lentera dan teh, mengirim Jun untuk
mengatakan pada penjaga agar membiarkan
Ishida masuk.
Si tabib tiba: mereka saling memberi salam
dengan riang, seolah belum bertemu selama
enam bulan lamanya. Pelayan perempuan
menuang teh dan membawakan lagi air
panas, lalu Takeo menyuruhnya pergi.
Dilepasnya sarung tangan sutra yang me-
nutupi tangan cacatnya dan Ishida menarik
lentera lebih dekat agar bisa melihatnya. Di-
tekannya jaringan kulit yang tumbuh meng-
gantikan jaringan yang rusak dengan ujung
jarinya lalu melemaskan jari yang tersisa.
"Kau masih bisa menulis dengan tangan
ini?"
"Setelah berlatih berulang kali. Aku me-
nulis dengan tangan kiri." Diperlihatkannya
pada Ishida. "Rasanya aku masih bisa ber-
tarung menggunakan pedang, tapi tidak ada
alasan untuk itu selama bertahun-tahun."
"Tidak kelihatan memerah karena infeksi,"
kata Ishida akhirnya. "Aku akan mencoba
dengan jarum besok, untuk mengiris garis
bujurnya. Untuk sementara waktu, ini akan
membantumu untuk tidur."
Selagi menyiapkan teh, Ishida bicara
dengan suara pelan, "Aku sering membuat
ini untuk istriku. Aku takut bertemu Kono;
hanya mengetahui putranya berbaring di
dalam kediaman ini, telah mengorek banyak
kenangan. Aku ingin tahu apakah dia seperti
ayahnya."
"Aku belum pernah bertemu Fujiwara."
"Kau beruntung. Aku menjalankan perin-
tahnya, selama hampir seumur hidupku. Aku
tahu dia orang yang kejam tapi dia selalu
memperlakukan diriku dengan baik, menye-
mangatiku untuk belajar dan melakukan
perjalanan, mengijinkan aku melihat koleksi
buku-bukunya yang berharga juga harta
benda yang lainnya. Kupalingkan wajahku
dari kegermarannya yang keji. Aku tidak
pernah menyangka kekejamannya akan
menimpa diriku."
Tiba-tiba Ishida berhenti bicara dan
menuang air mendidih ke atas herba kering.
Aroma samar-samar dari rumput musim
panas menyeruak, harum dan menenang-
kan.
"Istriku pernah cerita sedikit tentang saat-
saat itu," sahut Takeo pelan.
"Hanya gempa yang menyelamatkan kami.
Belum pernah aku begitu ketakutan, meski-
pun pernah menghadapi berbagai macam
bahaya: badai di laut, kapal karam, perompak
dan orang primitif. Aku pernah menghempa-
skan diri di bawah kakinya dan memohon
agar diijinkan bunuh diri. Dia berpura-pura
mengabulkannya, mempermainkan rasa
takutku. Terkadang aku memimpikannya;
sesuatu yang tak akan pulih dalam diriku;
sungguh suatu perwujudan iblis dalam diri
manusia."
Ishida berhenti sebentar, tenggelam dalam
kenangannya. "Saat itu anjingku melolong,"
tuturnya dengan amat pelan. "Bisa kudengar
anjingku melolong. Dia selalu memperingat-
kanku tentang gempa dengan cara seperti itu.
Kutemukan diriku bertanya-tanya apakah
ada orang yang memeliharanya."
Diambilnya mangkuk lalu diberikan pada
Takeo, "Aku mohon maaf yang sedalam-
dalamnya atas keterlibatanku dalam memen-
jarakan istrimu."
"Semua itu sudah berlalu," sahut Takeo,
seraya mengambil mangkuk tadi lalu me-
nenggaknya sampai habis dengan rasa
syukur.
"Namun bila putranya sama seperti ayah-
nya, dia hanya akan menyakitimu. Waspada-
lah."
"Kau memberiku obat dan memperingat-
kanku dalam satu tarikan napas," ujar Takeo.
"Mungkin aku memang harus menahan rasa
sakit inipaling tidak untuk membuatku
tetap terjaga."
"Aku harus berada di sini bersamamu..."
"Jangan. Kirin membutuhkanmu. Anak
buahku ada di sini untuk menjagaku. Untuk
sementara ini aku tidak dalam bahaya."
Takeo berjalan melewati taman bersama
Ishida sampai ke gerbang, merasa lega karena
rasa sakitnya mulai berkurang. Ia tidak
terjaga lamahanya cukup lama untuk
menghitung kejadian luar biasa hari ini:
Kono, ketidaksenangan Kaisar. Si Pemburu
Anjing, kirin dan adiknya: apa yang akan
dilakukannya dengan Madaren, perempuan
milik si orang asing. salah satu kaum
Hidden, adik perempuan Lord Otori?*
Melihat kakak laki-laki yang dikiranya sudah
tiada, bagi perempuan yang dulunya
dipanggil Madaren tak kurang terkejutnya,
nama yang biasa dipakai kaum Hidden.
Selama bertahun-tahun setelah peristiwa
pembantaian. Madaren berganti nama men-
jadi Tomiko, nama yang diberikan perempu-
an yang membelinya dari prajurit Tohan.
Prajurit yang turut ambil bagian dalam
pemerkosaan dan pembunuhan ibu serta
kakak perempuannya, namun Maraden tidak
ingat semua dari kejadian itu: yang diingat-
nya hanyalah hujan musim panas, bau
keringat kuda ketika pipinya menempel di
lehemya, tangan laki-laki yang memegangi
tubuhnya, tangan yang sepertinya lebih besar
dan lebih berat dibandingkan sekujur tubuh-
nya. Semuanya berbau asap dan lumpur dan
sadar kalau ia takkan bersih lagi. Saat awal
terjadinya kebakaran, kuda kuda dan pedang,
ia berteriak memanggil ayahnya, memanggil
Tomasu, seperti yang dilakukannya pada
awal tahun itu ketika terjatuh ke sungai
berarus deras dan terjebak di bebatuan sungai
yang licin, dan Tomasu mendengar teriakan-
nya dari sawah lalu berlari menghampiri
untuk menariknya keluar dari sungai, meng-
hardik juga menenangkannya.
Tapi kali ini Tomasu tidak mendengar
teriakannya; begitu pula ayahnya yang telah
tiada; tak seorang pun mendengar teriakan-
nya dan tak seorang pun datang menolong-
nya.
Banyak anak, tidak hanya yang hidup di
kalangan kaum Hidden, merasakan pen-
deritaan yang sama ketika Iida Sadamu
berkuasa di kastil berdinding hitam miliknya
di Inuyama; begitu pula dengan situasi yang
berubah setelah Inuyama jatuh ke tangan
Arai. Beberapa di antaranya bertahan hidup
hingga dewasa, Madaren merupakan salah
satunya, salah satu dari sejumlah besar gadis
yang melayani kebutuhan klas ksatria,
menjadi pelayan rumah, pelayan dapur atau
penghuni rumah pelacuran. Mereka tidak
punya keluarga, sehingga tanpa perlindung-
an; Madaren bekerja pada perempuan yang
membelinya, menjadi kelas terendah dari
pelayan, menjadi orang pertama yang bangun
di pagi hari dan tidak boleh tidur sebelum
pelanggan terakhir pulang. Ia mengira
kelelahan dan rasa lapar telah membuat diri-
nya kebal terhadap segala sesuatu di se-
kelilingnya, tapi saat dewasa dan segera men-
jadi gadis yang disukai, ia menyadari kalau
selama ini telah belajar dari gadis-gadis yang
lebih tua, dengan mengamati serta men-
dengarkan mereka, dan menjadi bijaksana
tanpa menyadarinya pada sasaranbenar,
satu-satunya sasaran mereka yaitu para laki-
laki yang datang berkunjung.
Rumah pelacuran barangkali merupakan
tempat yang paling kejam di Inuyama,
terletak jauh dari kastil di salah satu jalan
sempit yang terbentang di jalan utama,
tempat rumah-rumah kecil yang dibangun
kembali setelah kobaran api meluluh-
lantakkan semuanya bak sarang tawon yang
saling berdempetan. Tapi semua laki-laki
memiliki hasrat, bahkan kuli pengangkut
barang, buruh serta kuli angkut tanah di
malam hari, dan di antara mereka ini banyak
yang bisa diperdayai oleh cinta seperti laki-
laki golongan klas lainnya. Itulah yang
dipelajari Madaren; pada waktu yang ber-
samaan ia juga belajar bahwa perempuan
yang dikuasai cinta merupakan makhluk
yang paling tak berdaya di kota ini, dengan
mudahnya disingkirkan bak anak kucing
yang tidak diinginkan, dan ia memanfaatkan
apa yang dipelajarinya ini dengan cerdas. Ia
mau pergi dengan laki-laki yang dijauhi oleh
gadis-gadis lain, memanfaatkan rasa terima
kasih mereka. Ia bisa memeras hadiah dari
mereka, atau kadang mencurinya, dan pada
akhirnya membiarkan seorang pedagang yang
hampir bangkrut membawanya ke Hofu,
pergi meninggalkan rumah sebelum matahari
terbit lalu menemui laki-laki itu galangan
kapal yang masih berkabut. Mereka me-
numpang kapal yang mengangkut kayu cedar
dari hutan menuju wilayah Timur, dan
aroma kayu itu mengingatkannya pada
Mino, tanah kelahirannya. Hal itu meng-
ingatkannya pada keluarganya dan laki-laki
agak aneh yang menjadi kakaknya, yang
membuat gusar sekaligus memesona ibu
mereka. Air mata menggenang di matanya
saat meringkuk di bawah papan tebal, dan
ketika kekasihnya berbalik untuk memeluk-
nya. Madaren menampiknya. Pedagang itu
membosankan serta membuatnya gusar, dan
akhimya ia kembali ke kehidupan lamanya,
bergabung ke rumah pelacuran yang lebih
tinggi kelasnya dibandingkan yang pertama.
Kemudian orang-orang asing berjanggut
berdatangan, bau mereka yang aneh dan
tubuh mereka yang besar. Madaren melihat
ada semacam kekuatan dalam diri mereka
yang mungkin bisa dimanfaatkan dan dengan
sukarela tidur dengan mereka; ia memilih
orang yang bernama Don Joao, walaupun
laki-laki itu mengira kalau dialah yang
memilih Madaren: orang-orang asing bersifat
sentimental sekaligus pemalu bila sudah
berhubungan dengan kebutuhan jasmani:
mereka ingin merasa istimewa bagi seorang
perempuan, bahkan setelah mereka membeli-
nya. Mereka memberi bayaran yang memadai
dalam mata uang perak; Madaren berhasil
menjelaskan pada pemilik rumah bahwa Don
Joao hanya menginginkannya, dan tak lama
kemudian ia tidak harus tidur dengan laki-
laki lain.
Awalnya, bahasa mereka hanyalah bahasa
tubuh: nafsu si laki-laki, kemampuan si
perempuan memuaskannya. Orang-orang
asing sebelumnya memiliki seorang juru
bahasa, seorang nelayan yang mereka
selamatkan dari laut oleh kaum mereka
karena kapalnya tenggelam dan dibawa ke
markas mereka di Kepulauan Selatan.
Nelayan itu mempelajari bahasa mereka:
kadang menemani mereka ke rumah
pelacuran; jelas dari cara bicaranya kalau si
nelayan tidak berpendidikan dan berasal dari
klas rendahan, namun hubungannya dengan
orang asing memberinya status dan kekuasa-
an. Mereka bergantung sepenuhnya kepada-
nya. Nelayan itu merupakan pintu masuk
mereka ke dunia baru yang rumit, yang
mereka temukan dan mereka harapkan bisa
meraih kekayaan dan kemenangan. Mereka
percaya semua yang dikatakannya, bahkan
ketika dia hanya mengarang sembarangan.
Aku juga bisa meraih kekuasaan semacam
itu, karena nelayan itu tidak lebih baik dariku,
pikir Madaren, dan ia mulai berusaha me-
mahami Don Joao, lalu mendorong laki-laki
itu untuk mengajarinya. Bahasanya sulit,
penuh dengan bunyi aneh dan dikumpulkan
dari depan ke belakangsemuanya memiliki
jenis kelamin. Ia tak bisa membayangkan
alasannya, tapi pintu termasuk jenis
perempuan, begitu pula hujan; sedangkan
lantai matahari berjenis laki-lakitapi hal itu
justru memesonanya; dan jika bicara dengan
bahasa itu pada Don Joao, ia merasa seperti
menjadi orang lain. Karena Madaren sema-
kin fasihDon Joao tidak menguasai lebih
dari beberapa patah kata dari bahasa
Madarenmereka mulai membicarakan hal-
hal yang lebih mendalam. Don Joao mem-
punyai istri dan anak-anak di Porutogaru*,
kampung halamannya, orang-orang yang dia
tangisi ketika sedang mabuk. Madaren tidak
mengindahkan mereka, tak percaya kalau
Don Joao bisa bertemu mereka lagi. Mereka
begitu jauh hingga ia tak mampu
membayangkan seperti apa kehi-dupan
mereka, dan Don Joao bicara tentang
kepercayaan serta TuhannyaDeus**
dan kata-kata serta salib yang dikalungkan di
lehernya membangkitkan kenangan masa
kecil Madaren tentang kepercayaan keluarga-
nya dan ritual kaum Hidden.
Don Joao bicara penuh semangat tentang
Deus, dan menceritakan tentang pendeta
dalam agamanya yang berkeinginan kuat agar
negara lain menganut kepercayaan mereka.
Hal ini mengejutkan Madaren. Ia hanya
*) Porutogaru adalah lafal Jepang untuk menyebut
Portugal [pent.]
**) Deus berarti Tuhan dalam bahasa Portugal [pent.]
ingat sedikit tentang kepercayaan kaum
Hidden, hanya ingat gema doa serta ritual
yang dilakukan keluarganya dengan komu-
nitas kecil mereka. Penguasa baru Tiga
Negara, Otori Takeo, mengeluarkan ke-
putusan bahwa rakyatnya bebas beribadah
dan percaya pada kepercayaan pilihan me-
reka, dan prasangka lama pun perlahan
menghilang. Tentu saja, banyak yang tertarik
dengan agama orang asing dan bahkan
berkeinginan mencoba bila itu bisa mening-
katkan perdagangan dan kekayaan bagi
semua orang. Ada juga kabar burung yang
mengatakan bahwa Lord Otori dulunya
adalah orang Hidden, dan bahwa penguasa
Maruyama yang sebelumnya, Maruyama
Naomi, juga menganut kepercayaan itu. Tapi
menurut Madaren keduanya tak mungkin
melakukannyakarena bukankah Lord
Otori membunuh kakek pamannya untuk
balas dendam? Bukankah Lady Maruyama
menceburkan diri ke sungai di Inuyama ber-
sama putrinya? Satu hal yang diketahui
semua orang tentang kaum Hidden yaitu
Tuhan mereka, Tuhan Rahasia, melarang
mereka mencabut nyawa, baik nyawa mereka
sendiri maupun nyawa orang lain.
Pada titik inilah sepertinya Tuhan Rahasia
dan Deus berbeda, karena Don Joao men-
ceritakan kalau mereka adalah orang ber-
agama sekaligus prajurit. Apakah itu
keduanya atau tidak satu pun, selalu atau
tidak pernah, sudah atau belum? Don Joao
selalu bersenjatakan pedang panjang tipis,
penutup kepalanya berlekuk dan melindungi,
bertahtakan emas dan kerang mutiara, dan
membual bila dia selalu punya tujuan untuk
menggunakan pedang ini. Orang asing itu
terkejut karena penyiksaan dilarang di Tiga
Negara, dan menceritakan bagaimana ke-
kerasan digunakan di negaranya dan ter-
hadap penduduk asli Kepulauan lain untuk
menghukum, untuk mendapatkan informasi
serta menyelamatkan nyawa.
"Saat pendeta datang, kau harus dibaptis,"
kata Don Joao, dan ketika Madaren me-
mahami maksudnya, ia ingat yang sering
dikatakan ibunya: dilahirkan dengan air, lalu
menyebut nama baptisnya.
"Madalena!" ulang Don Joao dengan
terperanjat, lalu membuat gerakan berbentuk
tanda salib di depannya. Orang itu tertarik
setengah mati pada kaum Hidden, dan ingin
bertemu lebih banyak lagi penganutnya;
Madaren menangkap ketertarikannya dan
mereka mulai bertemu dengan para penganut
dalam jamuan makan di kalangan kaum
Hidden. Don Joao mengajukan banyak per-
tanyaan dan Madaren menerjemahkannya,
juga jawabannya. Madaren bertemu dengan
orang-orang yang mengetahui desanya dan
mendengar tentang pembantaian bertahun-
tahun yang lalu di Mino; menurut mereka, ia
bisa selamat merupakan mukjizat, dan
menyatakan kalau Madaren masih dibiarkan
hidup oleh Tuhan Rahasia untuk tujuan isti-
mewa tertentu. Madaren menyambut kem-
bali kepercayaan yang pernah hilang dari
masa kecilnya dengan hangat, lalu mulai
menunggu waktu untuk menjalankan misi.
Kemudian Tomasu dikirimkan padanya,
maka ia tahu misi itu berhubungan dengan
kakaknya.
Orang-orang asing hanya memahami
sedikit sekali tentang sikap dan kesopanan,
dan Don Joao berharap Madaren mene-
maninya kemana pun ia pergi, terutama
untuk menerjemahkan. Dengan keyakinan
mencapai tujuan yang dibawanya sejak
berhasil lolos dari Inuyama dan mempelajari
bahasa asing, ia mempelajari keadaan di
sekelilingnya yang masih asing, selalu ber-
lutut dengan rendah hati sedikit di belakang
orang-orang asing dan lawan bicara mereka,
bicara dengan pelan dan jelas, serta mem-
perindah terjemahannya bila terdengar
kurang sopan. Seringkali ditemukan dirinya
berada di rumah para pedagang, sadar akan
tatapan penuh hina serta kecurigaan dari
istri-istri dan anak perempuan mereka dan
bahkan kadang di tempat-tempat yang lebih
berkelas, terakhir bahkan di kediaman Lord
Arai. Ia merasa kagum pada dirinya sendiri,
satu hari berada di ruangan yang sama
dengan Lord Arai Zenko, lalu berikutnya di
penginapan semacam Umedaya. Nalurinya
ternyata benar: kemampuannya berbahasa
asing membuka jalan pada sebagian dari
kekuasaan serta kebebasan mereka. Dan
sebagian dari kekuasaan itu dia gunakan
untuk memanfaatkan orang-orang itu:
mereka membutuhkannya dan mulai meng-
andalkan dirinya.
Madaren pernah bertemu tabib Ishida
beberapa kali, dan bertindak sebagai juru
bahasa dalam perbincangan yang panjang;
Ishida kadang membawa teks-teks dan mem-
bacakannya untuk diterjemahkan karena
Madaren tidak bisa membaca maupun
menulis; Don Joao juga membacakan kitab
suci untuknya dan mengenali potongan-
poiongan kalimai dari doa dan pemberkatan
di masa kecilnya.
Malam itu Don Joao melihat Ishida lalu
memanggilnya, berharap bisa berbincang,
namun Ishida memohon pergi karena ada
pasien yang membutuhkannya. Madaren
menduga kalau pasiennya itu adalah kawan-
nya dan memelihat laki-laki yang satunya
lagi, memerhatikan tangannya yang cacat dan
kerutan di matanya. Ia tidak langsung
mengenalinya, namun jantungnya seperti
berhenti berdetak kemudian berdebar-debar,
seolah kulitnya mengenali laki-laki itu dan
segera mengenalinya kalau mereka lahir dari
ibu yang sama.
Madaren nyaris tak bisa tidur, menemu-
kan tubuh si orang asing di sebelahnya
teramat sangat panas, dan menyelinap keluar
sebelum matahari terbit, dan berjalan
menyusuri tepi sungai di bawah pohon
willow. Bulan melintasi langit dan kini
menggantung di barat, membulat serta pucat.
Ombak laut surut dan kepiting berlarian
cepat di atas lumpur yang mengering,
bayangan mereka tampak seperti tangan yang
sedang menggenggam. Madarien tidak ingin
mengatakan pada Don Joao kemana ia pergi:
tidak ingin harus berpikir dalam bahasa laki-
laki itu atau khawatir tentang laki-laki itu. Ia
berjalan melewati jalanan sempit menuju
rumah tempat ia dulu bekerja, membangun-
kan pelayannya, mandi dan berpakaian di
sana; lalu duduk tenang dan minum teh
hingga mentari pagi bersinar terang. Selama
berjalan ke Daifukuji, benak Madaren tersita
oleh keragu-raguan: kemarin itu bukan
Tomasu; dia salah lihat, memimpikan
tentang semuanya; dia takkan datang; jelas
sekali kalau kedudukannya amat tinggi, dia
seperti pedagang meskipun jelas bukan
pedagang yang berhasilyang tak ingin
punya hubungan apa-apa dengannya. Dia
tidak datang menghampiri untuk menolong-
nya; selama ini ternyata dia masih hidup dan
tidak berusaha mencarinya. Madaren berjalan
perlahan, melupakan aliran sungai yang
tergesa-gesa di sekelilingnya ketika gelom-
bang laut pasang menyapu.
Daifukuji menghadap ke laut: gerbang
merahnya bisa terlihat dari seberang ombak
laut, menyambut para pelaut dan pedagang
serta mengingatkan mereka untuk bersyukur
pada Ebisu, dewa laut, agar melindungi
mereka selama perjalanan. Madaren melihat-
lihat ukiran dan area di kuil itu dengan
perasaan tidak suka, karena ia telah percaya,
seperti halnya Don Jolo, kalau benda-benda
semacam itu dibenci Tuhan Rahasia dan
sama seperti menyembah setan. Ia bertanya-
tanya sendiri mengapa memilih tempat
seperti ini untuk bertemu, takut kalau kakak-
nya bukan lagi penganut kepercayaan,
menyelipkan tangannya di balik jubahnya
untuk menyentuh salib pemberian Don Joao,
dan menyadari pasti inilah misinya: menye-
lamatkan Tomasu.
Madaren berjalan masuk gerbang, me-
nunggu kakaknya, setengah tidak nyaman
dengan lantunan doa dan genta dari dalam
kuil, meskipun terpesona dan terbuai oleh
keindahan tamannya. Bunga lili menghiasi
tepian kolam, dan belukar azalea musim
panas pertama bermekaran menjadi bunga
berwarna merah tua. Sinar matahari terasa
makin panas dan bayangan taman semakin
menariknya masuk. Ia berjalan ke aula
utama. Di sebelah kanannya berdiri beberapa
pohon cedar tua, yang dililit tali jerami yang
berkilauan, dan tepat di belakangnya ter-
dapat kurungan berdinding putih di sekitar
taman dengan pepohonan yang jauh lebih
kecil, ia menduga itu pohon ceri walaupun
bunganya sudah lama gugur. Kerumunan
kecil sebagian besar rahib dengan kepala
botak dan jubah berwarna tidak mencolok,
berdiri di luar dinding, memandang ke atas.
Madaren mengikuti arah pandangan mereka
dan dan melihat apa yang sedang mereka
perhatikan: awalnya ia mengira itu, patung
ukiran, penggambaran semacam inkarnasi
perwujudan atau iblis kemudian benda itu
mengedipkan mata dengan bulu matanya
yang panjang, mengepakkan telinganya yang
datar, lalu menjilat hidungnya yang berwarna
coklat muda kekuningan lembut dengan
lidah abu-abu tuanya. Makhluk itu
memalingkan kepala bertanduknya dan
menatap ramah ke arah para pengagumnya.
Ternyata itu makhluk hidup: tapi makhluk
apa yang punya leher begitu panjang hingga
bisa melihat ke balik dinding yang lebih
tinggi dari manusia yang paling tinggi
sekalipun?
Itu adalah kirin.
Selagi Madaren memandangi hewan yang
luar biasa itu, kelelahan dan kebimbangan
dalam benaknya membuatnya serasa ber-
mimpi. Kemudian terlihat kesibukan dari
gerbang utama kuil, dan didengarnya suara
laki-laki berseru dengan penuh semangat,
"Lord Otori sudah datang!" Madaren seolah
tersentak dari mimpinya selagi berlutut lalu
melihat penguasa Tiga Negara itu berjalan
memasuki taman dan dikelilingi sebarisan
ksatria. Laki-laki itu mengenakan jubah
musim panas resmi berwarna krem dan emas,
dengan topi hitam kecil, namun dilihatnya
tangan cacat bersarung sutra, dan mengenali
wajahnya, dan menyadari kalau orang itu
adalah Tomasu, kakaknya.*
TAKEO sadar kalau adiknya tengah berlulut
dengan sikap rendah hati di bawah bayangan
di bagian samping taman, tapi ia tidak
memerhatikannya. Bila adiknya memang
akan tetap di situ, maka Takeo akan bicara
padanya berdua saja: bila dia pergi dan
menghilang lagi dari hidupnya, apa pun yang
dirasakannya entah kesedihan atau penye-
salan, ia takkan mencarinya. Bakal lebih baik,
mungkin juga lebih mudah, bila adiknya
menghilang. Akan cukup mudah untuk
mengaturnya: terbersit olehnya pikiran itu
namun kemudian menyingkirkannya jauh-
jauh. Takeo akan menangani adiknya dengan
adil, seperti yang akan dilakukannya pada
Zenko dan Kono: dengan perundingan,
menurut hukum yang telah dibuatnya
sendiri.
Seakan Surga makin menunjukkan
dukungannya, gerbang menuju taman yang
dikelilingi dinding terbuka dan kirin muncul.
Ishida mengendalikannya dengan seuntai tali
terbuat dari sutra merah yang diikatkan pada
untaian kalung mutiara. Tinggi kepala Ishida
tidak sampai setinggi bagian paling atas
punggung kirin, namun hewan itu
mengikutinya dengan sikap percaya diri
sekaligus berwibawa. Kulitnya berwarna
merah bata pucat, terpecah menjadi corak
bergaris bentuk berwarna krem berbentuk
dan sebesar telapak tangan manusia.
Hewan itu mengendus aroma air lalu
merentangkan leher panjangnya ke arah
kolam. Ishida membiarkannya mendekat,
lalu hewan itu merentangkan kaki ke
samping agar bisa menunduk untuk minum.
Kerumunan kecil biarawan dan prajurit
tertawa kegirangan karena tampak seolah
hewan mengagumkan itu membungkuk
hormat pada Lord Otori.
Takeo pun gembira melihat kejadian itu.
Ketika ia mendekat, hewan itu membiar-
kannya mengelus kulitnya yang lembut dan
bercorak indah itu. Hewan itu tampak tidakk
terlalu takut, walaupun lebih suka tetap
berada di dekat Ishida.
"Hewan ini jantan atau betina?" tanyanya.
"Kurasa, betina," jawab Ishida. "Hewan ini
tidak memiliki alat kelamin jantan, dan lebih
lembut dari yang bisa kuharapkan dari hewan
jantan sebesar ini. Tapi dia masih sangat
muda. Mungkin akan memperlihatkan
beberapa perubahan saat tumbuh semakin
besar, pada saat itulah kita bisa yakin."
"Di mana kau menemukannya?"
"Di selatan Tenjiku. Tapi dia berasal dari
pulau lain, masih jauh lagi ke barat; para
pelaut membicarakan tentang benua yang
amat besar tempat hewan-hewan seperti ini
merumput dalam jumlah besar bersama gajah
darat dan sungai, singa emas raksasa dan
burung berwarna merah muda. Orang-
orangnya berukuran dua kali lebih besar
daripada kita, berkulit sehitam warna pernis,
dan mampu membengkokkan besi dengan
tangan kosong."
"Dan bagaimana kau bisa mendapatkan-
nya? Tentunya hewan seperti ini tak ternilai
harganya?"
"Hewan ini ditawarkan padaku sebagai
semacam alat pembayaran," sahut Ishida.
"Aku berhasil mengobati seorang pangeran di
daerah itu. Aku langsung berpikir tentang
Lady Shigeko, dan betapa dia akan sangat
menyukainya, maka aku terima tawaran ini
dan mengatur agar hewan ini bisa menemani
kami pulang."
Takeo tersenyum memikirkan keahlian
putrinya dengan kuda dan kasih sayangnya
pada semua hewan.
"Tidakkah sulit untuk mempertahankan
agar dia tetap hidup? Apa makanannya?"
"Untungnya perjalanan pulang tidak ber-
ombak, dan kirin bersifat tenang serta mudah
dihibur. Makanannya dedaunan dari pohon
tempat asalnya, tapi ternyata se-nang juga
menerima rumput, segar atau pun kering,
serta dedaunan hijau yang lezat."
"Bisakah dia berjalan sampai ke Hagi?"
"Barangkali kita harus mengangkutnya
dengan kapal. Hewan ini bisa berjalan
bermil-mil jauhnya tanpa kelelahan, namun
kurasa tidak bisa berjalan melewati pe-
gunungan."
Ketika selesai mengagumi kirin, Ishida
membawa hewan itu kembali ke kandang,
kemudian pergi bersama Takeo menuju kuil,
tempat upacara singkat dilakukan, doa
dipanjatkan bagi kesehatan kirin dan Lord
Otori. Takeo menyalakan dupa dan lilin
serta berlutut di depan patung dewa; dilaku-
kannya semua praktik keagamaan yang
diharapkan darinya dengan khidmat dan
hormat; semua sekte dan kepercayaan
diperbolehkan di Tiga Negara, selama tidak
mengancam tatanan rnasyarakat. Ia sendiri
memercayai tuhan manapun, walau diakui-
nya keseluruhan manusia akan alasan
spiritual bagi keberadaan mereka, dan tentu
dirinya pun memiliki kebutuhan yang sama.
Setelah melakukan upacara, yang ada
penyembahan atas sang Pencerah dan Ebisu
dewa laut, teh dibawa masuk dengan
manisan osenbei. Takeo, Ishida dan Kepala
Biara setempat bercerita dengan gembira dan
menggubah puisi penuh dengan permainan
kata-kata tentang kirin.
Sesaat sebelum tengah hari, Takeo berdiri
dan mengatakan bahwa ingin sendirian di
taman sebentar, lalu berjalan menyusuri aula
utama ke aula yang lebih kecil di
belakangnya. Perempuan itu masih berlutut
dengan sabar di tempat yang sama. Takeo
memberi isyarat dengan gerakan tangan saat
berjalan melewatinya, meminta agar
perempuan itu mengikutinya.
Bangunan kuil menghadap ke timur; sisi
sebelah selatan bermandikan cahaya, namun
di beranda. di bawah bayangan gelap dari
atap yang melengkung, udara masih terasa
dingin. Dua rahib muda yang sedang
bertugas membersihkan patung dan
menyapu lantai mengundurkan diri tanpa
bicara. Takeo duduk di pinggiran beranda:
hayunya yang telah termakan cuaca berwarna
abu-abu ke-pcrakan dan masih hangat
terkena cahaya matahari. Terdengar olehnya
keraguan dalam langkah kaki Madaren di
atas kerikil jalan setapak, terdengar pula deru
napasnya yang cepat dan pendek. Burung
gereja berkicau di taman dan merpati
bergumam di pepohonan cedar. Madaren
berlutut lagi, menyembunyikan wajahnya.
"Tidak perlu takut," ujar Takeo.
"Ini bukan ketakutan," sahut Madaren
setelah beberapa saat. "Aku... tidak mengerti.
Mungkin aku telah melakukan kesalahan
besar. Tapi Lord Otori sekarang bicara
berdua saja denganku, yang tak akan pernah
terjadi kecuali dugaanku benar adanya."
"Kita saling mengenali semalam," ujar
Takeo. "Memang benar aku kakakmu. Tapi
sudah bertahun-tahun lamanya sejak terakhir
kali ada orang yang memanggilku Tomasu."
Madaren menatap langsung matanya;
Takeo tidak membalas tatapannya, malah
memalingkan wajah ke arah bayangan gelap
rumpun pepohonan, dan dinding di ke-
jauhan tempat kirin mengayunkan kepalanya
di atas genteng bak mainan anak-anak.
Ia sadar kalau ketenangannya tampak
seperti ketidakacuhan bagi Madaren, dan
juga tahu ada semacam amarah terpendam
dalam diri adiknya. Nada suara Madaren
nyaris terdengar seperti tuduhan.
"Selama enam belas tahun kudengar
balada dan cerita yang digubah tentang
dirimu. Kau tampak seperti pahlawan yang
jauh tak tergapai dan cuma legenda: bagai-
mana bisa kau adalah Tomasu dari Mino?
Apa yang terjadi padamu ketika aku dijual
dari satu rumah bordil ke rumah bordil
lainnya?"
"Aku diselamatkan Lord Otori Shigeru:
beliau mengangkatku menjadi pewarisnya
dan menginginkan aku menikah dengan
Shirakawa Kaede, pewaris Maruyama."
Itu garis besar paling sederhana dari
perjalanan luar penuh gejolak yang telah
menggiringnya menjadi orang paling ber-
kuasa di Tiga Negara.
Madaren bicara dengan nada kecut,
"Kulihat kau berdiri di hadapan patung
emas. Dan aku tahu dari cerita-cerita bahwa
kau pemah membunuh orang lain.."
Kepala Takeo bergerak sedikit untuk
membenarkan kata-kata adiknya. Seraya ber-
tanya-tanya apa yang diinginkan Madaren
darinya, apa yang bisa ia lakukan untuk
adiknya : apa saja, yang bisa memulihkan
hidupnya yang telah terlanjur hancur.
"Kurasa ibu dan kakak kita..." kata Takeo
dengan sedih.
"Keduanya sudah mati. Aku bahkan tidak
tahu di mana jasad mereka."
"Aku minta maaf atas semua penderitaan
yang telah kau alami." Takeo menyadari
bahkan saat ia bicara pun nada suaranya kaku
dan terlalu dibuat-buat, ia tak punya cukup
kata-kata untuk mengungkapkannya. Jarak
di antara mereka sudah terbentang terlalu
jauh. Tidak ada cara yang bisa mereka
lakukan untuk saling mendekati. Bila mereka
masih menganut kepercayaan yang sama
mungkin mereka bisa memanjatkan doa
bersama, namun kini kepercayaan masa kecil
yang dulu menyatukan mereka justru
menjadi penghalang yang tak bisa dilalui.
Mengetahui itu membuat ia tertekan dan iba.
"Jika kau butuh apa pun, kau bisa
mendekati pejabat kota yang berwenang,"
tutur Takeo. "Akan kupastikan kau diurus
dengan baik. Tapi aku tidak bisa
mengumumkan tentang hubungan kekeluar-
gaan kita, dan aku harus memintamu umuk
tidak mengatakannya pada siapa pun."
Takeo melihat kalau ia telah menyakiti
adiknya, dan rasa iba muncul lagi, tapi juga
tahu kalau ia tak bisa membiarkan adiknya
mengambil tempat lebih banyak lagi dalam
kehidupannya selain dengan cara seperti ini:
berada dalam perlindungannya.
"Tomasu," kata Madaren. "Kau adalah
kakakku. Kita saling memiliki kewajiban.
Kau satu-satunya keluargaku. Aku bibi dari
anak-anakmu. Dan aku pun memiliki tugas
spiritual terhadapmu. Aku peduli pada
jiwamu. Aku tak bisa melihatmu masuk
neraka!"
Takeo bangkit lalu berjalan menjauh.
"Tidak ada yang namanya neraka," sahutnya
sambil sedikit memalingkan wajah. "Selain
neraka yang diciptakan manusia di bumi.
Jangan coba-coba mendekatiku lagi."*
"Dan murid-murid pengikut Sang Pen-cerah
melihat macan dan anak-anaknya yang
sedang kelaparan," tutur Shigeko dengan
suaranya yang khidmat, "dan tanpa memikir-
kan nyawanya sendiri, mereka pergi ke tebing
yang sangat curam lalu menghempaskan diri
di bebatuan di bawahnya. Lalu macan-macan
itu bisa memakan mereka."
Sore itu terasa hangat di awal musim
panas, dan ketiga gadis itu diperintahkan
belajar di rumah sampai udara panas ber-
kurang. Selama beberapa saat mereka berlatih
menulis dengan rajin, lalu dengung meleng-
king jangkrik dan udara yang terasa lembut
membuat mereka mengantuk. Mereka sudah
keluar sebelum matahari terbit, dan sedikit
demi sedikit tubuh mereka menjadi lebih
santai dari posisi formal saat duduk menulis.
Shigeko dengan mudah terbujuk untuk
membuka gulungan gambar hewan lalu
membacakan ceritanya.
Namun sepertinya cerita yang paling baik
mesti memiliki moral cerita. Shigeko berkata
dengan khidmat, "Itulah contoh yang mesti
kita teladani; kita harus menyerahkan nyawa
kita agar bermanfaat bagi seluruh makhluk
yang berperasaan peka."
Maya dan Miki saling bertukar pandang.
Mereka amat menyayangi kakak mereka,
namun belakangan ini Shigeko terlalu gemar
menceramahi mereka.
"Aku lebih suka jadi macannya," ujar
Maya.
"Lalu memakan para murid yang mati
itu!" timpal adik kembarnya sepakat.
"Harus ada orang yang menjadi makhluk
yang berperasaan peka," bantah Maya ketika
melihat Shigeko mengernyitkan dahi.
Maya baru saja kembali setelah beberapa
minggu tinggal di Kagemura, desa ter-
sembunyi Muto, untuk berlatih dan meng-
asah bakat. Selanjutnya giliran Miki. Si
kembar jarang bersama; tanpa pernah
sepenuhnya mengerti sebabnya, dia tahu
kalau itu ada hubungannya dengan perasaan
ibu mereka. Kaede tidak suka melihat mereka
bersama. Wajah mereka yang serupa mem-
buat Kaede kesal. Sebaliknya, Shigeko selalu
membela mereka, bahkan saat tak bisa mem-
bedakan keduanya.
Mereka tidak suka berpisah, tapi akhimya
mulai terbiasa. Shizuka menenangkan mere-
ka, mengatakan kalau itu akan membuat
ikatan batin di antara mereka makin kuat.
Dan ternyata memang demikian adanya. Jika
Maya sakit, Miki pun sakit. Kadang mereka
bertemu dalam mimpi; mereka nyaris tidak
bisa melihat dengan jelas antara apa yang
terjadi di dunia lain dan apa yang terjadi
dunia nyata.
Saat-saat terbaik adalah ketika ayah
mereka datang ke desa rahasia Tribe, kadang
membawa salah satu dari mereka dan meng-
ajak yang satunya pulang. Selama beberapa
hari bersama, mereka menunjukkan apa yang
telah mereka pelajari dan kemampuan baru
yang mulai muncul. Dan Takeo yang ketika
di dunia Otori menjaga jarak dan bersikap
formal, di dunia Muto berubah menjadi
orang yang berbeda, guru seperti Kenji dan
Taku, memperlakukan mereka dengan
disiplin keras. Ketika mereka mandi bersama
di mata air panas dan menghujaninya dengan
cipratan, mereka menelusuri bekas luka di
badan ayahnya dan tak lelah mendengarkan
kisah di balik setiap bekas luka dmulai
dengan pertarungan melawan Kotaro ketua
Kikuta yang hingga ayah mereka kehilangan
dua jari di tangan kanannya.
Saat nama Kikuta disebut, si kembar tanpa
sadar menyentuh ujung jari mereka pada
lekukan yang melintang di telapak tangan
mereka, menandai diri mereka seperti sang
ayah, seperti Taku, sebagai Kikuta. Itu me-
rupakan lambang jalur sempit yang mereka
lalui di antara dunia.
Mereka tahu kalau sang ibu tidak
menyukai kemampuan Tribe yang mereka
miliki, dan bahwa klas ksatria menganggap
mereka penyihir: mereka belajar sejak dini
apa yang bisa dibanggakan di desa Muto
haruslah disembunyikan di kastil seperti
Hagi atau Yamagata, tapi terkadang godaan
untuk mengelabui guru-guru mereka, mem-
permainkan kakak perempuan mereka atau
menghukum orang yang lewat di depan
mereka sulit dibendung.
"Kau seperti aku ketika aku masih kecil,"
ujar Shizuka ketika Maya bersembunyi
selama setengah hari tanpa bergerak di dalam
keranjang bambu, atau ketika Miki
memanjat kayu kaso selentur dan secepal
kera liar, menghilang di balik atap yang
terbuat dari ilalang. Shizuka jarang marah.
"Nikmati saja," tuturnya. "Tidak ada yang
lebih menyenangkan."
"Kau beruntung Shizuka. Kau ada di sana
saat Inuyama jatuh! Kau bertarung bersama
Ayah!"
"Sekarang Ayah mengatakan tak akan ada
lagi perang; kita takkan menghadapi per-
tarungan yang sebenamya."
"Berdoa saja takkan ada perang lagi," ujar
Shigeko. Si kembar mengerang.
"Berdoalah seperti kakak kalian agar kalian
tidak pernah mengenal perang yang sebenar-
nya," Shizuka memperingatkan mereka.
Maya kembali ke pokok pembicaraan tadi.
"Jika tidak akan ada perang, mengapa Ayah
dan Ibu memaksa kami belajar kemampuan
bertarung?" tanyanya, karena ketiga gadis itu,
layaknya anak kelas ksatria, belajar memanah,
menunggang kuda serta menggunakan
pedang, diajarkan oleh Shizuka dan Sugita
Hiroshi atau ksatria besar lainnya di Tiga
Negara.
"Kata Lord Hiroshi siap perang adalah
pertahanan terbaik melawannya," sahut
Shigeko.
"Lord Hiroshi," bisik Miki, sambil menyi-
kut Maya. Kedua gadis kembar itu tertawa
cekikikan.
Wajah Shigeko bersemu merah. "Apa?"
tanyanya.
"Kau selalu mengatakan ucapan Lord
Hiroshi, lalu wajahmu bersemu merah."
"Aku tidak menyadari itu," kata Shigeko,
menutupi rasa malu dengan berbicara dengan
nada resmi. "Lagipula, itu tidak berarti apa-
apa. Hiroshi adalah salah satu guruyang
sangat bijaksana. Sudah sewajarnya aku
mempelajari peribahasa yang dipakainya."
"Lord Miyoshi Gemba juga salah satu
gurumu," ujar Miki. "Tapi kau jarang
mengutip apa yang dikatakannya."
"Dan Lord Miyoshi tidak membuat wajah-
mu merah!" timpal Maya.
"Kurasa kalian seharusnya bisa jauh lebih
baik dalam menulis, adik-adikku. Jelas sekali
kalian perlu banyak latihan. Ambil kuasnya!"
Shigeko membuka satu gulungan lagi| lalu
mulai mendiktekannya. Isinya adalah salah
satu hikayat kuno Tiga Negara, penuh
dengan istilah sulit dan kejadian yang sukar
dimengerti. Shigeko harus mempelajari
semua sejarah ini, begitu pula dengan si
kembar. Shigeko berharap pelajaran itu bisa
meng-hukum mereka karena menggodanya
soal Hiroshi, dan berharap mencegah mereka
membicarakan tentang topik itu lagi.
Shigeko memutuskan untuk lebih berhati-
hati, tidak membiarkan dirinya dengan
bodohnya menyebut nama Hiroshi.
Untungnya laki-laki itu sudah kembali ke
Maruyama untuk mengawasi hasil panen dan
persiapan upacara pengukuhan ia menjadi
pewaris wilayah itu.
Hiroshi sering menulis surat, karena dia
pengawal senior dan orangtuanya berharap ia
mengenal setiap detil wilayahnya. Surat-
suratnya bersifat resmi, tapi Shigeko suka
melihat tulisan tangannya, bergaya tulisan
tangan ksatria, tebal dan dibentuk dengan
baik. Surat-surat itu menyebut nama para
tetua serta karakter mereka, dan tentang
kuda. Hiroshi menceritakan dengan rinci
setiap anak kuda yang baru lahir dan
perkembangan kuda-kuda jantan yang
pernah mereka jinakkan bersama. Kuda-kuda
Maruyama sudah tumbuh satu tangan lebih
tinggi dibandingkan dua puluh tahun lalu,
ketika Hiroshi masih kecil.
Shigeko merindukannya dan amat ingin
berjumpa lagi dengannya: Hiroshi sudah
seperti kakaknya, tinggal di kediaman Otori,
dianggap sebagai putra dalam keluarga. Dia
mengajari Shigeko menunggang kuda, me-
manah serta bertarung dengan pedang:
Hiroshi juga mengajarinya seni perang,
strategi dan taktik, begitu pula dengan seni
pemerintahan. Lebih dari segalanya, Shigeko
berharap Hiroshi menjadi suaminya, tapi
menduga kalau itu tidak mungkin. Hiroshi
bisa menjadi penasihat yang paling berharga,
bahkan teman yang paling baik, tapi tidak
akan lebih. Ia pernah mendengar per-
bincangan soal pernikahan dirinya karena
kini usianya beranjak lima belas tahun. Ia
tahu akan ada rencana pertunangan, per-
nikahan yang akan memperkuat posisi
keluarganya dan menopang hasrat ayahnya
untuk kedamaian.
Semua pikiran ini melintas di benaknya
selagi membaca secara perlahan dan hati-hati
dari gulungan. Tangan si kembar terasa sakit
dan mata mereka terasa gatal saat Shigeko
selesai membacanya. Tak satu pun dari
keduanya berani berkomentar, dan Shigeko
mengurangi ketegasannya. Shigeko memper-
baiki pekerjaan adik-adiknya dengan baik
hati, cukup sering menyuruh mereka berlatih
lagi menulis huruf yang salah guratannya.
Ketika matahari mulai tenggelam dan udara
terasa agak dingin, Shigeko menyarankan
agar mereka berjalan-jalan sebelum latihan di
sore hari.
Si kembar, yang melemah dengan beratnya
hukuman yang mereka dapatkan, menye-
tujuinya dengan patuh.
"Kita ke biara," seru Shigeko, membuat
kedua adiknya bersorak kegirangan, karena
biara itu dipersembahkan bagi dewa sungai
dan kuda. "Bolehkah kita berjalan melewati
pagar penangkap ikan?" tanya Maya dengan
nada memohon.
"Tentu saja tidak bisa," sahut Shigeko.
"Tempat itu hanya boleh digunakan anak
berandalan, bukan putri-putri Lord Otori.
Kita akan berjalan menuju jembatan batu.
memanggil Shizuka dan memintanya untuk
ikut bersama kita. Dan kurasa kita sebaiknya
membawa beberapa pengawal."
"Kita tidak butuh pengawal."
"Bolehkah kami membawa pedang?" tanya
Maya dan Miki serempak.
"Untuk berkunjung ke biara, di jantung
Hagi? Kita tidak butuh pedang."
"Ingat serangan di Inuyama!" Miki meng-
ingatkan.
"Seorang ksatria sebaiknya selalu siaga,"
ujar Maya lumayan mirip menirukan
Hiroshi.
"Mungkin kau perlu latihan menulis lagi,"
balas Shigeko, kelihatan seakan ingin duduk
lagi.
"Baiklah, mari kita pergi seperti yang kau
katakan, kakak," sahut Miki cepat.
"Pengawal, tidak ada pedang."
***
Shigeko memikirkan selama beberapa saat
tentang masalah tandu: apakah memaksa si
kembar ditandu dalam kegelapan atau mem-
biarkan mereka berjalan kaki. Tak satu satu
pun dari keduanya ingin ditandu, tapi ia tahu
kalau Ibunya tidak suka si kembar terlihat
bersama di tempat umum. Di sisi lain, ini di
Hagi. kampung halaman mereka, tidak
seformal dan sekeras di Inuyama, dan kedua
adiknya yang gelisah mungkin bisa tenang
dan lelah setelah berjalan kaki. Shigeko pun
ingin berjalan kaki, ingin melihat kehidupan
kota yang penuh semangat, jalan-jalan
sempitnya serta toko-toko kecil penuh ber-
bagai hasil bumi dan kerajinan. Di belakang
jalan utama lebar yang mengarah dari
gerbang kastil menuju jembatan batu,
terbentang dunia yang sangat menyenang-
kan, tempat yang jarang bisa dikunjungi si
kembar.
Dua pengawal berjalan di depan mereka
dan dua lagi di belakang; satu pelayan
perempuan membawa keranjang bambu
berisi botol sake serta sesaji lain, termasuk
wortel untuk kuil kuda. Shizuka berjalan di
samping Maya, dan Miki berdampingan
dengan Shigeko. Mereka semua mengenakan
sandal kayu serta jubah tipis musim panas.
Shigeko memegang parasol, karena kulitnya
seputih kulit ibunya dan takut terkena sinar
matahari, tapi kulit si kembar kekuningan
seperti ayahnya merasa tidak perlu melin-
dungi kulit mereka.
Gelombang menghempas ketika mereka
tiba di jembatan batu, sungai berbau asin dan
lumpur. Di jembatan yang pernah hancur
dalam peristiwa gempayang dipercaya
rakyat sebagai hukuman atas pengkhianatan
Arai Daiichiada pahatan kalimat: Klan
Otori menyambut keadilan dan kesetiaan.
Waspadalah ketidakadilan dan ketidak-
setiaan.
"Lihat apa yang terjadi padanya!" ujar
Maya dengan nada puas selagi mereka berdiri
di depan batu itu. Mereka mempersembah-
kan sesaji sake, berterima kasih pada dewa
sungai karena melindungi Otori dan mem-
peringati tukang batu yang dikubur hidup-
hidup di dalam dinding itu bertahun-tahun
silam. Tulang belulangnya ditemukan di
sungai dan dikuburkan kembali selama
pembangunan kembali jembatan. Shizuka
sering menceritakan ini pada ketiga gadis itu,
juga cerita tentang putri si tukang batu,
Akane, dan terkadang mereka mengunjungi
kuil di kawah gunung berapi tempat
kematian tragis Akane diperingati dan
arwahnya yang dipanggil kembali oleh para
kekasih yang tidak bahagia, laki-laki maupun
perempuan.
"Shizuka pasti bersedih atas kematian Lord
Arai," kata Shigeko pelan saat mereka
meninggalkan jembatan, Sesaat si kembar
berjalan berdampingan: para pejalan kaki
berlutut ketika Shigeko lewat, tapi mema-
lingkan wajah ketika si kembar lewat.
"Aku bersedih atas cinta yang pernah ada
di antara kami," sahut Shizuka. "Juga untuk
kedua putraku, yang menyaksikan ayah
mereka mati di depan mata mereka. Tapi
Arai telah membuatku menjadi musuhnya,
dan telah memberi perintah agar aku di-
bunuh. Kematiannya tidak lebih dari akhir
yang adil atas cara hidup yang dipilihnya."
"Kau tahu banyak tentang masa-masa itu!"
seru Shigeko.
"Benar, barangkali lebih banyak dari siapa
pun," aku Shizuka. "Semakin usiaku ber-
tambah, semua yang terjadi di masa lalu
menjadi lebih jelas di benakku. Selama ini
Isihida dan aku mencatat semua ingatanku:
ayah kalian yang memintanya."
"Dan kau mengenal Lord Shigeru?"
"Namamu, Shigeko, adalah nama perem-
puan dari Shigeru. Ya, aku mengenalnya
dekat. Kami saling menaruh kepercayaan
satu sama lain selama bertahun-tahun, dan
saling percaya dengan taruhan nyawa kami.''
"Beliau pasti orang yang baik."
"Aku belum pernah bertemu orang seperti
dia."
"Apakah dia lebih baik ketimbang Ayah?"
"Shigeko! Aku tidak bisa menilai ayahmu!"
"Kenapa tidak? Ayah adalah sepupumu.
Kau mengenalnya lebih baik ketimbang
kebanyakan orang."
"Takeo sangat mirip Shigeru: dia seorang
laki-laki serta pemimpin yang hebat."
"Tapi...?"
"Semua orang memiliki kelemahan," tutur
Shizuka. "Ayahmu berusaha mcnguasai ke-
lemahannya, namun sifatnya terbagi dengan
cara yang tidak terjadi pada Shigeru."
Shigeko tiba-tiba merinding, meskipun
udara masih terasa hangat. "Jangan teruskan
lagi! Aku menyesal sudah bertanya."
"Ada apa? Apakah kau mendapatkan
firasat?"
"Aku selalu mendapatkan firasat," sahut
Shigeko pelan. "Aku tahu berapa banyak
orang yang menginginkan kematian ayahku."
Ia memberi isyarat pada si kembar yang
tengah menunggu di gerbang kuil. "Keluarga
kami terbelah dengan cara yang sama: kami
adalah gambaran dari sifat ayah. Apa yang
akan terjadi pada adik-adikku kelak? Di
mana tempat mereka di dunia ini?" Shigeko
bergidik lagi, dan berusaha mengubah topik
pembicaraan.
"Suamimu sudah kembali?" tanya Shigeko.
"Mungkin pulang dalam beberapa hari ini;
mungkin dia sudah di Hofu. Aku belum
mendengar kabarnya."
"Ayah sedang di Hofu! Mungkin mereka
bertemu di sana. Mungkin mereka akan
pulang bersama." Shigeko berbalik dan me-
natap kembali ke arah teluk. "Besok kita
akan mendaki bukit dan melihat apakah
kapal mereka sudah terlihat."
Mereka memasuki pintu kuil, lewat bagian
bawah gerbang besar. Di lengkungan gerbang
dipenuhi ukiran hewan dalam dongeng:
houou, kirin dan shishi. Kuil itu dibalut hijau-
nya tetumbuhan. Pepohonan willow besar
berbaris di tepi sungai; di samping pe-
pohonan tumbuh pohon oak dan cedar,
unsur terakhir dari hutan jaman purba yang
pernah menyelimuti tanah ini. Hiruk-pikuk
kota memudar menjadi senyap, hanya ter-
pecahkan oleh kicau burung. Arah cahaya
tampak miring dari barat menerangi debu di
sela-sela besarnya batang pohon dengan
pancaran sinar keemasan.
Seekor kuda putih di dalam istal berukiran
indah meringkik kelaparan melihat mereka,
dan si kembar pergi meinpersembahkan sesaji
bagi hewan yang dianggap keramat itu.
Seorang laki-laki tua muncul dari belakang
aula utama. Dia adalah seorang biarawan,
dan mengabdikan diri melayani dewa sungai
sejak kecil setelah kakaknya tenggelam di
pagar penangkap ikan. Namanya Hiroki.
Putra ketiga Mori Yusuke, pawang kuda dari
Klan Otori. Kakak laki-lakinya, Kiyoshige,
dulu adalah teman dekat Lord Shigeru.
Hiroki tersenyum sewaktu menghampiri
mereka. Dia memiliki ikatan khusus dengan
Shigeko melalui kecintaan mereka terhadap
kuda. Hiroki mempertahankan tradisi
keluarganya, merawat kuda Klan Otori
setelah ayahnya pergi ke ujung dunia dalam
rangka mencari kuda-kuda cepat dari tanah
datar yang luas. Yusuke sendiri tidak pemah
kembali, namun mengirimkan seekor kuda
hitam jantan yang menjadi ayah dari Raku
dan Shun, keduanya dijinakkan dan dilatih
oleh Takeshi, adik Shigeru, selama berbulan-
bulan sebelum kematiannya.
"Selamat datang, Lady!" Layaknya banyak
orang yang mengabaikan si kembar, seolah
keberadaan mereka terlalu memalukan untuk
diakui. Kedua gadis itu sedikit menarik din
di bawah bayangan pepohonan, memerhati-
kan si pendeta baik-baik dengan tatapan
mata yang sukar dimengerti. Shigeko melihat
kalau mereka marah. Terutama Miki yang
mempunyai sifat pemarah, yang belum
belajar cara mengendalikan amarahnya.
Watak Maya lebih dingin, namun lebih sulit
untuk diredam.
Setelah beramah tamah dan Shigeko
mempersembahkan sesaji, Hiroki menarik
tali genta untuk membangkitkan arwah dan
Shigeko memanjatkan doa, memandang diri-
nya sebagai penghubung antara dunia fana
dan dunia arwah bagi makhluk-makhtuk
yang tidak bisa bicara sehingga tidak ada doa.
Seekor anak kucing berlari terbirit-birit di
sepanjang beranda, mengejar sehelai daun
gugur. Hiroki menangkap kucing itu dengan
kedua tangannya, mengelus-elus kepala dan
telinganya. Kucing itu pun mendengkur
dengan suara parau. Matanya besar dan ber-
warna kuning kecoklatan, bola matanya me-
mantulkan cerahnya cahaya matahari, bulu
berwarna coklat muda pucat dengan bintik
hitam dan coklat kemerahan.
"Anda punya teman baru," seru Shigeko.
"Benar, dia datang mencari tempat tinggal
pada suatu malam saat hujan deras dan sejak
saat itu dia tinggal di sini. Dia teman yang
baik, kuda-kuda suka padanya, dan mem-
bungkam tikus-tikus."
Shigeko belum pemah melihat kucing
setampan itu; warna bulunya yang kontras
sungguh memukau. Dilihatnya Hiroki amat
menyayangi hewan itu, dan merasa senang.
Semua anggota keluarga Hiroki telah tiada:
dia hidup dengan menyaksikan kekalahan
Otori di Yaegahara hingga kehancuran kota
saat gempa. Satu-satunya hal yang menarik
baginya saat ini adalah melayani dewa sungai
dan kasih sayangnya pada kuda.
Si kucing membiarkan dirinya ditepuk-
tepuk selama beberapa saat, kemudian
meronta sampai Hiroki melepasnya. Kucing
itu pergi tergesa-gesa dengan ekor tegak
lurus.
"Akan terjadi badai," ujar Hiroki, tertawa
kecil. "Dia bisa merasakan cuaca di bulu-
bulunya."
Maya memungut sebatang ranting. Mem-
bungkuk lalu menggores dedaunan dengan
ranting itu. Kucing itu diam saja, tatapan
matanya tajam.
"Mari pergi melihat kuda," ajak Shigeko.
"Ikutlah bersamaku, Shizuka."
Miki berlari mengejar mereka, tapi Maya
tetap membungkuk di bawah bayangan,
membujuk si kucing untuk mendekat.
Sementara pelayan menunggu dengan sabar
di beranda.
Salah satu sudut di ladang kecil dipagari
bambu, dan seekor kuda jantan hitam di-
kurung di dalamnya. Tanah tempat si kuda
agak menanjak, rumputnya kering dan
banyak bekas jejak kaki. Saat melihat mereka,
kuda itu meringkik nyaring lalu bergerak
mundur. Dua kuda yang lebih muda berseru
menyahutinya. Mereka gelisah dan mudah
gugup. Keduanya memiliki bekas luka
gigitan baru di leher dan bagian sampingnya.
Seorang anak laki-laki lengah mengisi
ember air minum kuda hitam jantan itu.
"Dia sengaja menendang ember itu," gerutu-
nya. Di salah satu lengannya terlihat tanda
bekas gigitan dan lebam.
"Apakah dia menggigitmu?" tanya Shi-
geko.
Orang itu mengangguk. "Dia juga
menendangku." Diperlihatkannya lebam ber-
warna ungu gelap di betisnya.
"Aku tidak tahu apa yang harus dilaku-
kan," tutur Hiroki. "Dia selalu menyulitkan:
sekarang malah menjadi berbahaya."
"Dia tampan sekali," ujar Shigeko, menga-
gumi kaki panjang dan punggungnya yang
berotot, bentuk kepala yang sempuma dan
mata yang besar.
"Ya, dia memang tampan, juga tinggi:
kuda tertinggi yang kami miliki. Tapi dia
sangat keras kepala, aku tidak tahu apakah
dia bisa dijinakkan, atau apakah kita mesti
mengawinkannya."
"Tampaknya dia sudah siap dikawinkan!"
komentar Shizuka, dan mereka semua ter-
tawa karena si kuda memperlihatkan semua
gejala kuda jantan yang birahi.
"Aku khawatir menaruhnya bersama kuda
betina justru akan memperparah keadaan,"
tutur Hiroki.
Shigeko mendekati si kuda hitam jantan.
Bola mata kuda itu berputar dan telinganya
menegakkan.
"Hati-hati," Hiroki memperingatkan, dan
saat itulah si kuda mencoba menggigit
Shigeko.
Bocah pengurus kuda memukulnya ketika
Shigeko undur di luar jangkauan gigi si kuda.
Diamatinya kuda itu selama beberapa saat
tanpa bicara sepatah kata pun.
"Dikurung pasti membuat keadaannya
lebih buruk," ujarnya. "Pindahkan kuda yang
lebih muda dan biarkan dia memiliki ladang
ini sendirian. Bagaimana bila kau membawa
sepasang kuda betina yang tua dan mandul
apakah mereka bisa menenangkannya dan
mengajarinya sopan santun?"
"Gagasan yang bagus; aku akan mencoba-
nya," sahut si laki-laki tua, dan menyuruh
bocah tadi menuntun dua kuda tadi ke
padang rumput yang lebih jauh. "Kami akan
membawa kuda betina dalam satu atau dua
hari. Dia akan lebih menghargai teman bila
kesepian!"
Aku akan datang setiap hari dan melihat
apakah kuda ini bisa dijinakkan," kata
Shigeko, seraya berpikir akan menulis surat
pada Hiroshi dan menanyakan sarannya.
Mungkin Hiroshi akan datang dan mem-
bantuku menjinakkannya....
Shigeko tersenyum pada diri sendiri se-
waktu mereka kembali ke kuil.
Maya tengah duduk di beranda di sebelah
pelayan, matanya menatap ke bawah. Si
kucing tergeletak lemas di atas tanah, semua
keindahan dan semangat hidup kucing itu
tidak terlihat lagi.
Laki-laki tua itu menjerit, lalu bergegas
menghampiri, kemudian tersandung, ke arah
kucing itu. Diraihnya hewan itu lalu dipeluk-
nya erat-erat. Kucing itu bergerak tedikit,
tapi tidak bangun.
Shizuka langsung menghampiri Maya.
"Apa yang kau lakukan?"
Tidak ada," jawabnya. "Kucing itu
menatapku, lalu tertidur."
"Bangun, Mikkan," laki-laki tua itu
memohon dengan sia-sia. "Bangunlah!"
Shizuka menatap kucing itu dengan
perasaan panik. Dengan usaha yang kentara
mengendalikan reaksinya, dia berkata pelan,
"Kucing itu takkan bangun. Kalaupun ter-
bangun, tidak dalam waktu yang lama."
"Ada apa?" tanya Shigeko. "Apa yang
Maya lakukan pada kucing itu?"
"Aku tidak melakukan apa-apa," kata
Maya lagi, tapi dari tatapan matanya saat
mendongak, Maya terlihat seperti ke-
girangan. Dan ketika menatap Hiroki yang
mulai menangis pelan, bibirnya berkerut
dengan sinis.
Ketika tersadar, Shigeko berkata dengan
kesal, "Itu pasti salah satu kemampuan
rahasia, kan? Sesuatu yang dipelajarinya
sewaktu dia pergi? Kemampuan sihir yang
mengerikan!"
"Jangan bicarakan itu di sini," gumam
Shizuka, karena para pelayan kuil berkumpul
dan menatap dengan mulut menganga seraya
memegangi jimat. "Kita harus pulang. Maya
harus dihukum. Tapi mungkin sudah ter-
lambat."
"Terlambat untuk apa?' tanya Shigeko.
"Nanti kuceritakan. Aku hanya mengerti
sebagian tentang kemampuan Kikuta seperti
ini. Kuharap ayahmu ada di sini."
***
Shigeko bahkan lebih merindukan ayahnya
pulang saat menghadapi kemarahan ibunya.
Sorenya di hari yang sama: Shizuka mengajak
si kembar pergi untuk menghukum Maya,
dan mereka berdua diperintahkan tidur di
kamar yang terpisah. Badai menderu di
kejauhan, dan dari tempatnya berlutut,
kepala tertunduk di hadapan ibunya, dapat
Shigeko melihat cahaya samar di dinding
berhiaskan motif emas menonjol saat kilatan
halilintar tampak mengarah ke laut. Ramalan
cuaca si kucing ternyata benar.
Kaede berkata, "Seharusnya kau tidak ajak
mereka ke sana! Kau tahu kalau Ibu tak ingin
mereka terlihat berdua di depan umum."
"Maaf, Ibu," bisik Shigeko. Ia tidak ter-
biasa dengan kemarahan ibunya dan itu amat
menyakitkan baginya. Tapi ia juga khawatir
pada si kembar, dan merasa kalau ibunya
bersikap tidak adil pada mereka. "Hari ini
panas sekali; mereka sudah belajar dengan
giat. Mereka perlu pergi keluar."
"Mereka bisa bermain di taman sini,"
sahut Kaede. "Maya harus dikirim pergi."
"Ini musim panas terakhir yang akan kita
habiskan bersama di Hagi," Shigeko me-
mohon. "Biarkan dia tinggal setidaknya
sampai Ayah pulang."
"Miki masih bisa diatur, tapi Maya sudah
mulai tak terkendali," seru Kaede. "Dan tak
ada hukuman yang bisa membuatnya jera.
Berpisah dengan adiknya bisa menjadi cara
terbaik mengendalikannya. Juga akan mem-
buat kita lebih tenang selama musim panas!"
"Ibu...?" Shigeko mulai bicara, namun tak
mampu meneruskan kalimatnya.
"Aku tahu kau pikir Ibu bersikap keras
pada mereka," tutur Kaede setelah beberapa
saat terdiam. Kaede mendekat agar bisa
melihat wajah putrinya itu. Lalu dibelainya
rambut Shigeko yang panjang dan halus.
"Indahnya rambutmu! Seperti rambut Ibu
dulu!"
"Mereka berharap Ibu bisa menyayangi
mereka," Shigeko berani angkat bicara,
merasakan kalau amarah ibunya sudah reda.
"Mereka merasa dibenci Ibu karena mereka
bukan anak laki-laki."
"Ibu tidak membenci mereka," sahut
Kaede. "Ibu malu dengan kehadiran mereka.
Buruk sekali memiliki anak kembar, seperti
mendapat kutukan. Ibu merasa seperti men-
dapat semacam hukuman, peringatan dari
Surga. Dan kejadian atas kucing ini mem-
buat Ibu ketakutan. Seringkali Ibu berpikir
sebaiknya mereka mati saat lahir, seperti
kebanyakan anak kembar lainnya. Ayahmu
tak ingin itu. Dia membiarkan mereka tetap
hidup. Tapi kini Ibu bertanya pada diri
sendiri: apa tujuannya? Mereka putri
keluarga Otori; mereka tidak bisa pergi dan
tinggal bersama Tribe. Tak lama lagi usia
mereka akan cukup untuk dinikahkantapi
siapa dari kalangan klas ksatria yang mau
menikahi mereka? Siapa yang mau beristri
penyihir? Jika kemampuan mereka ter-
ungkap, para ksatria bahkan akan mem-
bunuh si kembar."
Shigeko merasakan tubuh ibunya gemetar.
"Ibu menyayangi mereka," bisik Kaede.
"Namun terkadang mereka membuat Ibu
sangat menderita dan ketakutan hingga Ibu
berharap mereka mati saja. Dan Ibu selalu
merindukan kehadiran anak laki-laki, dan
tidak bisa berpura-pura bersikap sebaliknya.
Masalah siapa yang akan menikah denganmu
juga menyiksa Ibu. Dulu Ibu berpikr
sungguh anugerah yang tak terkira bisa
menikah dengannya. Namun Ibu juga sudah
melihat kalau itu bukannya tanpa pengor-
banan. Ibu bertindak bodoh dan egois
dengan berbagai macam cara. Ibu menentang
semua yang diajarkan sejak kecil, yang
diharapkan dan disarankan untuk melak-
sanakannya, dan mungkin harus menebusnya
selama sisa hidup Ibu. Ibu tak ingin kau
mengulangi kesalahan yang sama, terutama
karena kami tidak punya anak laki-laki, maka
memilih suamimu menjadi masalah politis."
"Aku sering dengar Ayah bilang kalau
Ayah bahagia kalau seorang gadisaku
akan mewarisi Tiga Negara."
"Begitulah yang selalu dikatakannya.
Hanya untuk menghibur Ibu. Semua laki-
laki ingin anak laki-laki."
Namun Ayah kelihatannya tidak begitu,
pikir Shigeko. Tapi perkataan ibunya, nada
penyesalan yang terkandung di dalamnya,
serta keseriusan dalam nada suaranya, mem-
bekas di dalam hatinya.*
Berita kematian Muto Kenji memerlukan
waktu berminggu-minggu untuk sampai ke
Inuyama. Kikuta ingin merahasiakannya
selama mungkin sambil berusaha menyela-
matkan para tawanan, tapi mereka juga ingin
menyebarkan berita itu untuk menunjukkan
pada Otori bahwa di luar Tiga Negara, dia
tidak berdaya.
Selama pemerintahan Takeo dan Kaede,
jalan-jalan di seluruh Tiga Negara telah
diperbaiki dan pesan-pesan dibawa dengan
cepat antar kota-kota besar. Tapi di luar
wilayah Timur, tempat Barisan Awan Tinggi
membentuk penghalang alami, terbentang
bermil-mil negeri tak bertuan sampai ke kota
bebas Akashi, pelabuhan yang membentuk
gerbang masuk ke ibukota Kaisar, Miyako.
Desas-desus tentang kematian Muto Kenji
terdengar di Akashi kira-kira di bulan
keempat, dan dari sana kabar itu tersiar
hingga ke Inumaya melalui pedagang yang
sering meneruskan kabar berita dari wilayah
Timur kepada Muto Taku.
Walaupun sudah menduganya, Taku
merasa sedih juga marah atas berita itu. Ia
merasa seharusnya Kenji mati dengan damai
di kampung halamannya sendiri, karena
kematian seperti itu akan dianggap
kelemahan di mata Kikuta dan hanya akan
membuat mereka lebih bersemangat. Ia
berdoa agar kematian Kenji terjadi dengan
cepat dan bukannya tanpa makna.
Taku merasa harus memberitahukan kabar
itu pada Takeo, dan Sonoda juga Ai setuju
kalau ia harus segera bewingkat ke Hofu,
tempat Takeo pergi untuk beberapa alasan
pemerintahan, sementara Kaede dan anak-
anaknya sudah kembali ke Hagi selama
musim panas.
Keputusan atas nasib tawanan juga harus
secara resmi dilaksanakan baik oleh Takeo
maupun Kaede. Mungkin mereka akan
dieksekusi sekarang, tapi harus dilakukan
sesuai hukum agar tidak dianggap sebagai
tindakan balas dendam. Taku sendiri
mewarisi sifat sinis Kenji dan tidak enggan
melakukan tindakan balas dendam, namun
dia menghormati ketegasan Takeo pada
keadilanatau setidaknya memberi kesan
adil. Kematian Kenji juga memengaruhi
Tribe, karena dia sudah menjadi ketua lebih
dari dua puluh tahun: seorang keluarga Muto
harus dipilih untuk menggantikan keduduk-
annya. Kakak Taku, Zenko, merupakan
kerabat laki-laki terdekat karena Kenji hanya
memiliki seorang putri yang sudah mati,
Yuki, namun Zenko mengambil nama
keluarga ayahnya dan tidak memiliki ke-
mampuan Tribe. Apalagi kini dia berstatus
sebagai ksatria berkedudukan tertinggi,
pimpinan Klan Arai yang memimpin wilayah
Kumamoto.
Orang yang tersisa hanyalah Taku yang
sudah jelas oinat berbakat dalam kemampuan
menghilang serta menggunakan sosok kedua,
dilatih oleh Kenji, dipercaya oleh Takeo.
Satu alasan lagi untuk mengadakan per-
jalanan saat ini yaitu untuk bertemu keluarga
Tribe, untuk memastikan kesetiaan dan
dukungan mereka serta membahas tentang
siapa yang akan menjadi Ketua.
Lagipula Taku merasa gelisah: ia sudah di
Inuyama sepanjang musim dingin. Istrinya
menyenangkan, anak-anak menghiburnya,
tapi kehidupan rumah tangga membuatnya
bosan; diucapkannya selamat tinggal pada
keluarganya tanpa penyesalan, dan meskipun
misinya membawa kabar menyedihkan, ia
bersiap pergi keesokan harinya dengan lega
bercampur penuh harapan, menunggang
kuda pemberian Takeo kepadanya saat masih
kecil: anak dari Raku, kuda dengan kulit
abu-abu pucat, surai dan ekor sehitam arang
warna yang amat dihargai di Tiga Negara.
Taku menamainya Ryume.
Ryume sudah menjadi ayah dari banyak
kuda jantan, dan kini sudah tua, namun ia
tak pernah menyukai kuda seperti kuda yang
satu ini, yang dijinakkannya sendiri serta
tumbuh dewasa bersama dirinya.
Saat ini bukan waktu yang tepat untuk
melakukan perjalanan, hujan musim semi
baru saja mulai turun, tapi berita itu tidak
bisa ditunda lagi, tak ingin orang lain yang
membawa berita ini. Taku berkuda dengan
cepat meskipun di tengah cuaca buruk,
seraya berharap bisa bertemu Takeo sebelum
meninggalkan Hofu.
***
Kedatangan kirin dan pertemuan dengan
adik perempuannya mencegah Takeo untuk
pergi secepatnya ke Hagi seperti yang
diinginkannya. Keponakannya, Sunaomi dan
Chikara bersiap-siap melakukan perjalanan,
namun badai hebat| menunda keberangkatan
mereka selama dua hari. Itulah sebabnya
Takeo masih berada di Hofu ketika Muto
Taku datang dari Inuyama ke rumah kakak-
nya, meminta segera dipertemukan dengan
Lord Otori. Sangat jelas bahwa Taku mem-
bawa berita buruk. Ia tiba hampir malam,
kelelahan dan tubuhnya yang kotor karena
berjalan jauh, tapi tidak ingin mandi atau
makan sebelum bicara dengan Takeo. Tidak
ada rincian, hanya kenyataan keji bahwa
Muto Kenji sudah tiada. Tak ada jenazah
yang bisa ditangisi, tak ada batu nisan untuk
menandai makamnya: cara kematian yang
paling sulit untuk ditangisi, jauh dan tak
terlihat. Kesedihan Takeo memuncak,
semakin diperburuk oleh keputusasaannya.
Namun ia merasa tak mampu menumpahkan
perasaannya di rumah Zenko, dan tak
mampu menahan Taku sepenuhnya sesuai
dengan kehendaknya. Diputuskannya untuk
pergi ke Hagi keesokan harinya, dan
menunggang kuda dengan cepat. Keinginan
utamanya adalah bertemu Kaede, agar
istrinya itu bisa menghiburnya. Namun
kekhawatirannya yang lain tak bisa dising-
kirkan dan menunggu sementara ia meng-
hadapi kesedihannya. Setidaknya ia harus
membawa salah satu putra Zenko; Sunaomi
yang akan dibawanyabocah itu pasti bisa
menunggang kuda dengan cepatlalu
mengirim adiknya bersama Ishida dan kirin
dengan naik kapal begitu cuaca membaik.
Taku bisa mengurusnya. Dan Kono?
Mungkin Taku bisa tinggal di wilayah Barat
untuk mengawasinya. Berapa lama lagi
sampai ia bisa mendapat kabar dari Fumio?
Berhasilkah dia menggagalkan penyelun-
dupansenjata api? Dan jika tidak berhasil,
berapa lama lagi waktu yang mereka
butuhkan untuk menandingi jumlah per-
senjataan miliknya?
Kenangan tentang gurunya dan masa lalu
menghujani dirinya. Ia berduka tidak hanya
karena kehilangan Kenji, tapi juga ke-
hilangan semua yang berhubungan dengan-
nya. Kenji sahabat Shigeru: satu mata rantai
lagi yang terputus.
Lalu masalah tawanan di Inuyama yang
harus dihukum mati, namun harus dilakukan
sesuai hukum, dan ia atau salah satu anggota
keluarganya harus hadir. Ia harus menulis
surat pada suami Ai, Sonoda, mengirim
perintah agar Ai menggantikan Kaede, se-
suatu tugas yang akan menciutkan nyali adik
iparnya yang berhati lembut itu.
Takeo terjaga semalaman hanya ditemani
kesedihan. Saat matahari terbit, ia memang-
gil Minoru dan mendiktekan surat untuk
Sonoda dan Ai, tapi sebelum membubuhkan
cap, ia berbicara lagi dengan Taku.
"Aku merasa enggan untuk memerintah-
kan hukuman mati kedua pemuda-pemudi
itu. Apakah ada cara lain?"
"Mereka hendak membunuh keluargamu,"
sahut Taku. "Kau yang membuat aturan dan
hukuman. Apa yang akan kau lakukan pada
mereka? Memaafkan lalu membebaskan me-
reka justru akan kelihatan seperti kelemahan;
dan dipenjara dalam waktu lama lebih kejam
ketimbang kematian dengan cara cepat."
"Tapi apakah kematian mereka akan men-
cegah serangan-serangan selanjutnya? Bukan-
kah ini semakin membangkitkan amarah
Kikuta pada diriku dan keluargaku?"
"Dendam Akio padamu sudah mutlak
sifatnya. Ia tak akan mundur selama kau
masih hidup," sahut Taku, lalu menambah-
kan, "Namun kematian akan menyingkirkan
dua pembunuh lagi, dan cepat atau lambat
mereka akan kehabisan orang yang mau dan
mampu melakukannya. Kau harus hidup
lebih lama daripada mereka."
"Kau seperti Kenji," ujar Takeo. "Sama
realistis dan pragmatisnya seperti Kenji.
Kurasa kau yang akan mengambil alih
kepemimpinan keluarga sekarang?"
"Aku akan bicarakan dengan ibuku. Dan
kakakku, tentu saja, demi formalitas. Zenko
hanya memiliki sedikit kemampuan Tribe,
dan mengambil nama ayah kami, tapi tetap
saja dia lebih tua dariku."
Takeo menaikkan alis sedikit. Ia lebih suka
menyerahkan penanganan masalah pada
Kenji dan Taku, memercayai Kenji sepenuh-
nya. Ia merasa tak nyaman dengan pemikiran
harus berbagi rahasia mereka dengan Zenko.
"Kakakmu mengusulkan agar aku meng-
angkat salah satu putranya," tutur Takeo,
membiarkan nada terkejut terdengar dalam
suaranya, yang diketahuinya tak akan luput
dari perhatian Taku. "Sunaomi akan
menemaniku ke Hagi. Aku akan berangkat
sebentar lagi. Tapi ada banyak hal yang harus
kita bicarakan terlebih dulu. Mari berjalan-
jalan di taman."
"Lord Otori," Minoru mengingatkannya.
"Tidakkah Anda harus menyelesaikan surat-
nya lebih dulu?"
"Tidak, bawa saja bersama kita. Aku akan
membicarakan masalah itu lebih jauh lagi
dengan istriku sebelum aku memutuskan.
Kita akan mengirimnya dari Hagi."
Sinar matahari yang baru terbit tampak
kelabu, pagi terasa lembap dan basah, dengan
hujan yang mengancam akan turun. Per-
jalanan itu akan basah dan tidak nyaman.
Takeo sudah bisa memperkirakan bagai-
mana rasa sakit pada luka lamanya akan
memperburuk hari-hari selama menunggang
kuda. Ia sadar kalau Zenko mungkin sedang
mengawasinya, membenci kedekatannya
dengan Taku, tahu kalau dirinya akan
menaruh kepercayaan pada adiknya. Meng-
ingat kalau Zenko juga keluarga Muto, serta
ada hubungan saudara dengan Kikuta, mem-
buatnya selalu siaga. Berharap benar adanya
kalau Zenko tak memiliki kemampuan
Tribe, Takeo menceritakan dengan pelan
pada Taku secara singkat tentang pesan Lord
Kono, begitu pula dengan masalah
penyelundupan senjata.
Taku menyerap semua penjelasan ini
dalam diam; satu-satunya komentar darinya,
"Kurasa, kepercayaanmu pada kakakku
sudah terkikis."
"Kakakmu telah memperbarui sumpah
setianya padaku, tapi kita semua tahu
sumpah setia tidak ada artinya bila ber-
hadapan dengan ambisi akan kekuasaan.
Kakakmu selalu menyalahkanku atas
kematian ayahmudan kini sepertinya
Kaisar dan kalangan istananya pun ber-
anggapan sama. Aku tidak memercayai
kakakmu maupun istrinya, tapi selama kedua
putra mereka di tanganku, kurasa ambisi
mereka masih bisa dibendung. Ambisi
mereka harus dibendung: alternatif lainnya
adalah akan terjadi perang saudara lagi atau
aku harus memerintahkan kakakmu bunuh
diri. Aku akan menghindari ini selama
mungkin. Tapi aku harus memintamu
menutup mulut lebih rapat dari biasanya,
dan tidak mengungkap apa pun yang bisa
menguntungkan dirinya."
Kebiasaan Taku dalam ekspresi sinisme
yang senang, menjadi lebih gelap lagi.
"Aku yang akan membunuhnya bila dia
mengkhianatimu," sahutnya.
"Jangan!" sahut Takeo cepat. "Jangan
sekali-kali membunuh saudara kandung.
Masa-masa pertumpahan darah antar
keluarga telah berakhir. Kakakmu, seperti
juga semua orangtermasuk dirimu sendiri,
Takuharus dibatasi Hukum." Ia berhenti
sesaat, kemudian berkata pelan, "Tapi
katakan: apakah Kenji pernah mengatakan
ramalan tentang diriku, bahwa aku aman dari
kematian, kecuali di tangan putraku sendiri?"
"Ya pernah, setelah salah satu percobaan
pembunuhan padamu, dia berkomentar
mungkin ramalan itu benar adanyatak
biasanya paman percaya pada ramalan dan
pertanda. Saat itu paman menceritakan apa
yang telah dikatakan tentang dirimu. Paman
menceritakan itu sebagian untuk menjelas-
kan ketidaktakutanmu, dan mengapa
ancaman serangan tidak melumpuhkan diri-
mu atau membuatmu bertindak kejam,
seperti yang akan dilakukan sebagian besar
orang."
"Aku juga tidak mudah percaya," sahut
Takeo, sambil tersenyum penuh penyesalan.
"Kadang aku percaya kebenaran kata-kata
itu, kadang tidak. Ramalan itu membuat aku
percaya karena telah memberiku waktu
untuk meraih segala yang kuinginkan tanpa
ketakutan. Bagaimana pun juga, anak itu
kini berusia enam belas tahun: cukup usia,
dalam kalangan Tribe, untuk membunuh.
Maka kini aku merasa terjebak: dapatkah aku
berhenti percaya ketika ramalan itu tidak lagi
sesuai dengan keadaanku?"
"Bakal cukup mudah untuk menyingkir-
kan bocah itu," Taku menawarkan.
"Taku, kau tidak belajar apa-apa dari
semua jerih payahku! Masa-masa pem-
bunuhan rahasia sudah berakhir. Aku tak
mampu mencabut nyawa kakakmu ketika
pisauku di lehernya saat sengitnya per-
tempuran. Aku tak akan memerintahkan
untuk membunuh putraku sendiri."
Setelah beberapa saat Takeo melanjutkan,
"Siapa lagi yang tahu tentang ramalan ini?"
"Saat Kenji menceritakan hal ini padaku,
tabib Ishida ada di sana. Dia sedang meng-
obati luka dan mencoba meredakan demam-
mu. Kenji mengatakan itu untuk meya-
kinkan Ishida bahwa kau takkan mati, karena
tabib itu hampir menyerah."
"Zenko tidak tahu?"
"Dia tahu keberadaan putramudia di
desa Muto ketika berita kematian Yuki
datang. Semua orang terus membicarakannya
selama berminggu-minggu. Tapi kurasa
Kenji tidak menceritakan soal ramalan itu
pada orang lain."
"Maka biarkan ramalan itu tetap menjadi
rahasia."
Taku mengangguk. "Aku akan tinggal di
sini bersama mereka, seperti yang kau
sarankan," ujarnya.
"Awasi dengan baik, pastikan kalau
Chikara berangkat bersama Ishida, dan
mungkin cari tahu lebih banyak lagi tentang
niat orangtuanya yang sebenarnya."
Sewaktu mereka berpisah, Taku berkata,
"Satu hal lagi. Bila kau mengangkat Sunaomi
sebagai anak, dan dia menjadi putramu...."
"Saat itu aku akan memilih untuk tidak
percaya!" sahut Takeo pura-pura bicara
dengan nada ringan yang justru tidak dirasa-
kannya." *
Takeo berangkat kira-kira pada Waktu Ular*
di mana hujan belum turun, namun
menjelang malam hujan turun dengan deras.
Sunaomi diam saja, bersemangat untuk ber-
sikap dengan benar dan berani. namun jelas
terlihat kalau dia khawatir meninggalkan
orangtua dan keluarganya. Dua pengawal
Zenko ikut untuk mengurusnya. Sementara
Takeo didampingi Jun dan Shin, dua puluh
prajurit serta Minoru. Di malam pertama
mereka menginap di desa kecil, tempat
beberapa penginapan dibangun selama masa
kemakmuran negara ini. Desa ini acapkali
menjadi tempat transit para pedagang yang
melakukan perjalanan antara Hofu dan Hagi.
Jalanan terawat dengan baik, dilapisi batu
kerikil atau diratakan setiap jengkalnya;
setiap kota kecil dijaga sehingga perjalanan
menjadi aman dan cepat. Meskipun hujan,
mereka sampai di sungai pada sore di hari
ketiga, dan bertemu Miyoshi Kahei yang
sudah diberitahu kurir bahwa Lord Otori
* Waktu Ular: berkisar antara jam 09.00 s/d Jam 11.00. (peny)
dalam perjalanan ke utara.
Atas kesetiaannya pada Takeo, Kahei
dianugerahi kota Yamagata dan daerah-
daerah yang mengelilinginya, hutan lebat
yang membentuk jantung Negara Tengah
serta tanah pertanian yang kaya di kedua sisi
sungai. Yamagata dulu diserahkan pada
Tohan setelah kekalahan Otori di Yaega-
hara. Keluarga Miyoshi merupakan salah satu
keluarga terhebat dalam Klan Otori, dan
Kahei merupakan pemimpin yang disukai
banyak orang. Dia juga pemimpin yang ahli
strategi dan taktik sehingga, pikir Takeo,
Kahei pasti menyesali tahun-tahun yang
penuh kedamaian dan merindukan konflik
baru untuk menguji keabsahan teori-teori-
nya serta kekuatan dan ketrampilan pasukan-
nya. Adiknya, Gemba. lebih bersimpati pada
keinginan Takeo untuk mengakhiri ke-
kerasan, dan menjadi murid Kubo Makoto
dan pengikut Ajaran Houou.
"Kau akan ke Terayama?" Kahei bertanya
setelah mereka saling memberi salam dan
menunggang kuda berdampingan ke utara,
menuju ke kota.
"Aku belum memutuskan," jawab Takeo.
"Bukannya aku tidak menginginkannya, tapi
aku tak ingin tertunda sampai di Hagi."
"Apa sebaiknya kukirim kabar ke biara
agar mereka datang ke kastil?'"
Takeo melihat tidak ada lagi cara meng-
hindar tanpa menyinggung perasaan sahabat
lamanya ini. Takeo pikir tidak ada salahnya
kalau Sunaomi berkunjung ke tempat suci
Klan Otori, ziarah ke makam Shigeru,
Takeshi dan Ichiro, serta bertemu Makoto
dan para ksatria lain dengan kematangan
spiritual yang menjadikan biara itu pusat
kegiatan serta rumah mereka. Sunaomi
tampak pandai sekaligus sensitif: Ajaran
Houou mungkin bisa menjadi ajaran yang
tepat baginya, seperti yang telah terbukti
pada putrinya, Shigeko. Ia merasakan per-
cikan ketertarikan yang tak terduga: betapa
indahnya memiliki seorang putra untuk
dibesarkan dan dididik dengan ajaran ini;
timbulnya kekuatan emosi ini mengejutkan
dirinya. Segala iiamnya sesuatunya diatur
untuk pergi pagi-pagi keesokan harinya.
Minoru tinggal di Yamagata untuk meng-
awasi rincian administratif dan menyiapkan
bukti catatan yang akan diperlukan untuk
pengadilan nanti.
Hujan berubah menjadi kabut: wajah
bumi terselubung awan kelabu; di atas
pegunungan langit tampak bermain, dan
balutan awan seputih mutiara tampak bak
umbul-umbul di lereng. Air hujan mem-
bentuk torehan garis pada batang pepohonan
cedar, meneteskan embun. Langkah kuda
diredam oleh tanah yang basah. Mereka
berkuda tanpa bicara; nyeri yang dirasakan
Takeo ternyata tidak separah dugaannya, dan
benaknya penuh dengan kenangan akan
kunjungannya yang pertama ke biara ini
beserta orang-orang yang menunggang kuda
bersamanya bertahun-tahun lalu. Orang yang
paling diingatnya, terutama Muto Kenji,
nama paling baru yang dituliskan di buku
besar nama orang-orang yang telah tiada.
Kenji yang dalam perjalanan itu berpura-
pura menjadi kakek-kakek yang bodoh,
gemar minum sake dan lukisan. Aku menya-
yangimu. Aku tidak ingin kehilanganmu.
Takeo merasakan kesendirian yang menyakit-
kan, karena kematian Kenji meninggalkan
kekosongan besar dalam hidupnya yang tak
akan bisa terisi lagi, dan sekali lagi ia merasa
rapuh, serapuh yang pernah dirasakannya
setelah bertarung dengan Kikuta Kotaro yang
telah membuat tangannya cacat. Kenji
mengajarinya cara mempertahankan diri
dengan menggunakan tangan kiri, men-
dukung dan memberi nasehat di masa-masa
awal berkuasa di Tiga Negara, memecah
Tribe dan membawa empat dari lima
keluarga di bawah kekuasaannya, semua
keluarga kecuali Kikuta, dan mempertahan-
kan jaringan mata-mata yang menjaga Takeo
dan negara agar tetap aman.
Pikirannya lalu melayang ke satu-satunya
keturunan Kenji yang masih hidup, cucunya,
yang ditahan Kikuta.
Putraku, pikirnya dengan penyesalan,
kerinduan serta kemarahan. Dia tak pernah
mengenal ayah maupun kakeknya. Dia tak-
kan memanjatkan doa yang dibutuhkan bagi
nenek moyangnya. Tak ada orang lain lagi
yang bisa menghormati kenangan akan
Kenji. Bagaimana kalau aku mencoba men-
dapatkan anak itu kembali?
Tapi itu berarti mengungkap keberadaan
anak itu pada istri serta ketiga putrinya, pada
seluruh negara. Rahasia itu telah tersembunyi
sekian lama hingga Takeo tidak tahu bagai-
mana mengutarakannya. Andai Kikuta mau
berunding agar bisa diberi semacam hak
khusus. Kenji telah menduga kalau mereka
mungkin mau; dia memilih untuk mendekati
Akio, dan kini dia telah tiada, dan dua
pemuda lagi akan kehilangan nyawa sebagai
hasilnya. Seperti Taku, Takeo ingin tahu
berapa banyak lagi pembunuh yang Kikuta
miliki, tapi tidak seperti Taku, ia tidak
bersemangat bila jumlahnya makin ber-
kurang.
Jalan setapak itu sempit sehingga mereka
dalam kelompok kecilSunaomi dan kedua
pengawalnya, kedua pengawal Takeo serta
tiga ksatria Otori lainnya, ditambah dua anak
buah Kaheiberkuda dalam satu barisan.
Tapi setelah mereka meninggalkan kuda di
tempat penginapan di kaki gunung suci,
Takeo memanggil Sunaomi agar berjalan
bersamanya, menceritakan padanya sedikit
tentang sejarah biara, tentang pahlawan-
pahlawan Otori yang dimakamkan di sana,
tentang houou, burung suci yang bersarang di
hutan kecil di belakang biara, dan ksatria
yang mengabdikan dirinya pada Ajaran
Houou.
"Kami akan mengirimmu kemari bila kau
sudah lebih besar; putriku datang ke sini
setiap musim dingin, dan sudah melaku-
kannya sejak usia sembilan tahun."
"Aku akan melakukan apa saja yang
paman inginkan," sahut bocah itu. "Aku
berharap bisa melihat burung houou dengan
mata kepalaku sendiri!"
"Kita akan bangun pagi-pagi sekali dan
pergi ke hutan kecil itu sebelum kembali ke
Yamagata. Hampir dipastikan kau bisa
melihat burung itu karena sekarang jumlah-
nya banyak."
"Chikara melakukan perjalanan bersama
kirin," seru Sunaomi, "dan aku ber-
kesempatan melihat houou. Itu adil. Tapi.
Paman, apa yang harus dipelajari untuk
mengikuti Ajaran Houou?"
"Orangorang yang akan kita temui yang
akan memberitahukan: biarawan seperti
Kubo Makoto; ksatria seperti Miyoshi
Gemba. Ajaran utamanya yaitu tidak meng-
inginkan kekerasan."
Sunaomi tampak kecewa. "Jadi aku tidak
akan belajar memanah dan berpedang? Itu
yang ayah ajarkan pada kami, dan ayah ingin
kami mahir dalam keduanya."
"Kau akan melanjutkan pelatihan bersama
putra-putra ksatria di Hagi, atau di Inuyama
saat kita sudah sampai. Tapi Ajaran Houou
sangat menuntut pengendalian diri, dan juga
kekuatan fisik serta mental. Mungkin kau
tidak cocok dengan ajaran ini."
Takeo melihat cahaya berkilap di mata
bocah itu. "Kuharap diriku cocok dengan
ajaran ini," sahut Sunaomi, setengah ber-
teriak.
"Putri sulungku akan menceritakan lebih
banyak lagi tentang ajaran ini begitu kita tiba
di Hagi."
Takeo hampir tidak bisa mengucapkan
nama kota itu, begitu besar keinginannya
untuk berada di sana dan bersama Kaede.
Tapi ia berusaha menyembunyikan perasaan-
nya dengan cara yang sama seperti yang
dilakukannya seharian berusaha menyem-
bunyikan rasa nyeri dan penderitaannya. Di
gerbang biara mereka disambut dengan
kegembiraan, dan seorang biarawan diminta
untuk memberitahukan Kepala Biara,
Matsuda Shingen, dan Makoto tentang
kedatangan mereka. Mereka dikawal menuju
griya tamu. Meninggalkan Sunaomi dan
anak buahnya di sana, Takeo berjalan
melewati taman, melewati kolam ikan tempat
ikan air tawar merah dan keemasan ber-
desakan dan mencipakkan air, menuju hutan
kecil suci di belakang biara, menyusuri
tanjakan terjal jalan pegunungan, tempat
para bangsawan Otori dimakamkan.
Kabut lebih tebal menyelimuti tentera
abu-abu dan batu nisan yang dipersuram
oleh embun dan bintik-bintik lumut hijau
dan putih. Lumut yang berwarna hijau tua
menutupi bagian dasarnya. Ada seutas tali
rami baru berkilauan di sekeliling makam
Shigeru, dan sekerumunan orang berdiri
menundukkan kepala di depan makam,
berdoa bagi laki-laki yang telah menjadi
pahlawan dan perwujudan dewa, kekuatan
Negara Tengah dan Klan Otori. Sebagian
besar dari mereka adalah petani, pikir Takeo,
mungkin ada satu atau dua pedagang dari
Yamagata yang turut serta. Ketika melihat ia
mendekat, mereka langsung mengenalinya
dari lencana di jubahnya, dari tangan yang
terbungkus sarung tangan hitam. Mereka
menjatuhkan diri ke tanah, namun Takeo
memberi salam lalu menyuruh mereka
berdiri, kemudian meminta meninggalkan
dirinya sendiri di dekat makam. Takeo
berlutut, menatap sesaji yang ada di sana,
segenggam penuh bunga warna merah tua,
kue mochi dan sake.
Masa lalu muncul di sekelilingnya, dengan
semua kenangan menyakitkan. Ia berhutang
nyawa pada Shigeru; dan telah menjalani
hidupnya sesuai dengan tujuan sang men-
diang. Wajahnya basah karena kabut dan air
mata.
Terasa ada gerakan di belakangnya, dan
Takeo berbalik melihat Makoto berjalan
menghampiri sambil membawa lentera di
satu tangan dan tempat dupa kecil di tangan
yang satunya lagi. Makoto berlutut lalu
meletakkan kedua benda itu di depan
makam. Asap ketabu naik perlahan, berat,
bercampur kabut, memenuhi udara dengan
aromanya. Lentera menyala dengan tenang,
menerangi suramnya hari ini.
Dalam waktu lama mereka berdua tidak
bicara sepatah kata pun. Kemudian genta
berdentang dari pelataran biara, dan Makoto
berkata, "Mari masuk dan makan. Kau pasti
lapar. Senang sekali bertemu denganmu."
Mereka berdua bangkit dan saling
mengamati. Mereka pertama kali bertemu
tepat di tempat ini, tujuh belas lahun lalu,
sempat timbul rasa saling menyukai di
mereka berdua, dan untuk sesaat kasih
sayang di antara mereka begitu kuatnya bak
sepasang kekasih. Makoto pernah bertempur
bersama Takeo di Asagawa dan Kusahara dan
selama bertahun-tahun menjadi teman ter-
dekatnya. Karena sudah begitu mengenal
Takeo, Makoto merasakan bila sahabatnya
itu sedang menghadapi masalah, maka
Makoto bertanya, "Apa yang terjadi?"
"Aku akan menceritakannya dengan cepat.
Muto telah tiada. Dia pergi untuk berunding
dengan keluarga Kikuta dan tidak kembali.
Aku akan ke Hagi untuk memberitahukan
kabar ini pada keluargaku. Kami akan ke
Yamagata besok."
"Aku turut berduka atas kehilangan ini.
Kenji teman yang setia. Tentu saja kau ingin
bersama Lady Otori di saat seperti ini. Tapi
haruskah kau pergi begitu cepat? Maaf, tapi
kau tampak lelah. Tinggallah selama
beberapa hari di sini untuk memulihkan
kekuatanmu."
Takeo tersenyum, tergoda oleh ajakan itu,
merasa iri pada Makoto dengan penampilan-
nya yang sempurna secara fisik dan spiritual-
nya. Makoto saat ini berusia tiga puluhan,
tanpa kerutan di wajahnya yang tenang; sinar
matanya penuh kehangatan dan kegembira-
an. Seluruh sikapnya memancarkan
ketenangan dan pengendalian diri. Takeo
yakin kalau teman lamanya yang satu lagi,
Miyoshi Gemba pasti kelihatan sama,
layaknya para pengikut ajaran ini. Takeo me-
rasakan ada sedikit penyesalan karena jalan
hidup yang memanggilnya untuk dijalani
sangat berbeda. Seperti yang selalu
dilakukannya saat mengunjungi Terayama, ia
berangan-angan mengundurkan di sini,
mengabdikan diri dengan melukis dan
merancang taman seperti seniman besar
Sesshu; ia akan menyumbangkan Jato
pedang yang selalu ia bawa meskipun tak lagi
digunakan selama bertahun-tahunlalu
berhenti menjalani hidup sebagai ksatria dan
penguasa. Bersumpah untuk tidak mem-
bunuh lagi, melepaskan diri dari kekuasaan
atas hidup dan mati setiap orang di negara
ini, membebaskan diri dari beban yang berat
dan menyakitkan di balik kekuatan ini.
Suara-suara biara yang tidak asing lagi
menyelimuti dirinya. Dengan sadar dibuka-
nya gerbang pendengarannya dan membiar-
kan suara-suara itu menyirami dirinya,
percikan air terjun di kejauhan, gumaman
doa dari aula utama, suara Sunaomi dari
griya tamu, desingan layang-layang dari
puncak pepohonan. Dua burung gereja hing-
gap di ranting, bulu warna abu-abu mereka
tampak jelas dengan sinar agak redup serta
gelapnya warna dedaunan. Dibayangkannya
bagaimana ia bisa melukis mereka.
Namun tak ada orang lain yang bisa
mengambil alih perannya: mustahil bisa
menjauh dari semua itu.
"Aku baik-baik saja," ujarnya. "Aku
minum terlalu banyak, tapi sake meredakan
rasa sakitku. Ishida memberiku minuman
pengurang rasa sakit, tapi aku sudah kebal
dengannyaaku jarang-jarang meminum-
nya. Kami akan menginap semalam di sini:
aku ingin putra Arai melihat biara ini dan
bertemu denganmu. Dia akan tinggal ber-
sama keluargaku. Mungkin aku akan
mengirimnya kemari dalam satu atau dua
tahun lagi."
Dahi Makoto berkerut. "Zenko sedang
buat masalah?"
"Lebih dari biasanya. Dan ada perkem-
bangan di wilayah Timur yang harus
kuceritakan padamu. Aku harus merencana-
kan jawabanku dengan hati-hati. Bahkan
mungkin aku harus pergi ke Miyako. Kita
akan bicarakan hal iiu nanti. Bagaimana
kabar Lord Matsuda? Aku juga berharap bisa
mendapatkan saran darinya."
"Beliau masih bersama kami," sahut
Makoto. "Jarang makan, bahkan sepertinya
tidak pernah tidur. Tampaknya beliau sudah
separuh berada di dunia lain. Tapi pikiran-
nya masih tetap jernih, bahkan mungkin
lebih jernih, seperti danau di pegunungan."
"Kuharap pikiranku ada di sini," ujar
Takeo, selagi mereka berjalan kembali ke
biara. "Tapi pikiran lebih menyerupai salah
satu kolam ikan itu: penuh gagasan dan
masalah juga sampah di sekelilingnya,
masing-masing berusaha menarik perhatian-
ku."
"Kau seharusnya mencoba menenangkan
pikiran setiap harinya," Makoto mengamati.
"Satu-satu kemampuan meditasi yang
kumiliki adalah kemampuan Tribedan
tujuannya agak berbeda!"
"Tapi bila kuamati kemampuan itu begitu
memang ada dalam dirimu dan anggota
Tribe lainnya, sangat berbeda dengan kami
yang harus melalui disiplin diri dan
pengenalan diri."
Takeo tidak setuju: ia belum pernah
melihat Makoto atau murid-muridnya meng-
gunakan kemampuan menghilang, atau
menggunakan sosok kedua. Dirasakannya
keraguan Makoto, dan menyesalinya.
"Aku tak punya waktu bermeditasi, lagi-
pula aku hanya mendapat sedikit pelatihan
atau pendidikan tentang ajaran itu. Dan aku
tidak tahu kalau itu bisa membantu. Aku
terlibat dalam pemerintahan... paling tidak,
saat ini, jika tidak bisa disebut peperangan."
Makoto tersenyum. "Kami di sini men-
doakanmu setiap waktu."
"Kukira itu bisa membuat perbedaan!
Mungkin doa kalian yang telah memper-
tahankan kedamaian selama hampir lima
belas tahun."
"Aku yakin begitu," sahut Makoto tenang.
"Bukan hanya doa yang hampa atau lantunan
pujian tanpa makna, tapi keseimbangan
spiritual yang kami pertahankan di sini.
Kupakai kata "mempertahankan" untuk me-
nunjukkan otot dan kekuatan yang dibutuh-
kan; kekuatan pemanah untuk mem-
bengkokkan busur atau balok di menara
lonceng untuk menahan berat lonceng."
"Aku percaya. Aku melihat perbedaan
dalam diri para ksatria yang mengikuti
ajaranmu: disiplin dan welas asih mereka.
Tapi bagaimana ini bisa membantuku
menghadapi Kaisar dan jenderal barunya,
yang akan memerintahkan aku mengasing-
kan diri?"
"Saat kau ceritakan semuanya nanti, kami
akan berikan saran untukmu," Makoto ber-
janji. "Kita makan dulu, lalu kau ber-
istirahat."
***
Setelah selesai makan siang sederhana yang
terdiri dari sayuran, sedikit nasi, dan sop,
hujan mulai turun dengan derasnya. Cahaya
mulai meredup, kehijauan, dan tiba-tiba
keinginan untuk berbaring tak tertahankan
lagi. Makoto mengajak Sunaomi bertemu
dengan beberapa murid yang masih muda;
Jun dan Shin duduk di luar, minum teh dan
berbincang-bincang dengan suara pelan.
Takeo tertidur, rasa sakitnya berkurang
seolah luruh dengan bunyi rintik hujan bak
gendang bertalu-talu di aiap. Ia tidak ber-
mimpi, dan terbangun dengan pikiran yang
lebih jernih. Lalu mandi di mata air panas,
menge-nang ketika ia berendam di kolam
yang sama saat salju turun sewaktu melarikan
diri ke Terayama bertahun-tahun lalu.
Setelah selesai berpakaian, Takeo melangkah
ke beranda tepat saat Makoto dan Sunaomi
kembali.
Takeo menyadari kalau bocah itu ter-
sentuh oleh sesuatu. Wajahnya bersinar dan
matanya berkilauan.
"Lord Miyoshi menceritakan bagaimana
dia hidup di pegunungan sendirian selama
lima tahun. Beruang memberinya makan,
dan pada malam-malam yang dingin mem-
beku meringkuk memeluknya agar tetap
hangat!"
"Gemba ada di sini?" tanya Takeo pada
Makoto. "Dia kembali saat kau tidur. Dia
sudah tahu kau ada di sini."
"Bagaimana Lord Miyoshi bisa tahu?"
tanya Sunaomi.
"Lord Miyoshi tahu hal-hal semacam ini,"
sahut Makoto sambil tertawa.
"Apakah beruang-beruang itu yang mem
beri tahunya?"
"Kemungkinan begitu! Lord Otori, mari
kita menemui Kepala Biara."
Meninggalkan Sunaomi bersama kedua
pengawal pribadinya, Takeo berjalan bersama
Makoto melewati aula tempat makan di
biara, tempat rahib-rahib muda mem-
bereskan mangkuk bekas makan malam,
menyeberangi sungai kecil yang dialihkan
airnya agar mengalir melewati dapur, dan ke
pelataran di depan aula utama. Di dalam aula
utama ada ratusan lentera dan lilin yang
menyinari patung emas Sang Pencerah, dan
Takeo mengenal sosok tanpa suara yang
sedang duduk bermeditasi di dalamnya.
Mereka mengikuti jalan setapak terbuat dari
papan menyeberangi satu cabang lagi aliran
sungai kecil menuju aula tempat lukisan
Sesshu, dan menghadap ke taman. Hujan
telah reda, malam telah menjelang dan be-
batuan di taman tampak seperti bayangan
hitam, nyaris tak terlihat. Harum lembut
bunga serta tanah yang basah merebak ke
dalam aula. Bunyi air terjun kedengaran
lebih keras di sini. Di ujung cabang utama
sungai kecil, yang mengalir di sepanjang
taman dan menuruni gunung, berdiri griya
tamu perempuan tempat Takeo dan Kaede
menghabiskan malam pertama pernikahan
mereka. Tempat itu kini kosong; tak ada
cahaya yang bersinar dari dalamnya.
Matsuda sudah berada di aula, bersandar
pada bantalan tebal yang disangga dua rahib
tanpa suara dan tidak bergerak. Matsuda
sudah tua saat pertama kali Takeo bertemu
dengannya; kini sepertinya dia telah melewati
jauh dari batasan usia yang mengekang,
bahkan batasan kehidupan, dan telah me-
masuki dunia jiwa yang suci.
Takeo berlutut lalu membungkuk sampai
ke lantai di hadapannya. Matsuda adalah
satu-satunya orang di Tiga Negara yang
paling dihormatinya.
"Mendekatlah," ujar Matsuda. "Biar ku-
lihat dirimu. Biar kusentuh dirimu."
Kasih sayang dalam nada suaranya mem-
buat Takeo terharu. Dirasakannya air mata
mengambang ketika laki-laki tua itu men-
condongkan badan ke depan lalu menepuk-
kan tangan. Mata Matsuda mencari-cari
wajah Takeo; merasa malu akan air mata
yang sebentar lagi tumpah, Takeo tidak
membalas tatapannya malah melihat ke
belakang, ke lukisan-lukisan Sesshu indah.
Waktu tidaklah bergerak bagi lukisan-
lukisan itu, pikirnya. Kuda, bangaumereka
masih seperti dulu, sedangkan begitu banyak
orang yang pernah melihat mereka kini telah
tiada, terbang jauh bak burung gereja. Satu
satu kasa yang kosong, menurut legenda,
lukisan burung-burung itu begitu hidup
hingga akhimya terbang.
"Jadi Kaisar merasa khawatir dengan diri-
mu," ujar Matsuda.
"Putra Fujiwara, Kono, datang berpura-
pura mengunjungi tanah milik ayahnya, tapi
sebenarnya dia memberitahuku bahwa aku
telah membuat Kaisar merasa tidak senang
bahkan dianggap penjahat; aku diminta
untuk mengundurkan diri dan mengasingkan
diri."
"Aku tidak kaget kalau Kaisar bingung dan
takut padamu," Matsuda tertawa kecil. "Aku
hanya terkejut mengapa begitu lama baru
mereka mengancammu."
"Kurasa ada dua alasan; pertama Kaisar
memiliki jenderal baru yang telah menakluk-
kan wilayah Timur dan sekarang pasti meng-
anggap dirinya cukup kuat untuk meman-
cing kita. Alasan yang lainnya adalah Arai
Zenko telah berhubungan dengan Kono.
Aku mencurigai Zenko menganggap dirinya
sebagai penerusku."
Takeo merasakan amarahnya meletup lagi,
dan segera menyadari kalau Matsuda dan
Makoto melihatnya. Di saat bersamaan,
diperhatikannya ada satu orang lain berada di
dalam aula, duduk di bawah bayangan di
belakang Matsuda. Orang ini mencondong-
kan badan ke depan sekarang, dan Takeo
sadar kalau orang itu adalah Miyoshi Gemba.
Usia mereka hampir sebaya, tapi seperti hal-
nya Makoto, Gemba nampak tidak berubah
seiring dengan berjalannya waktu. Gemba
memandangnya dengan tatapan lembut,
santai namun penuh kekuatanhampir
seperti beruang.
Sesuatu terjadi pada lentera. Cahayanya
berkedip-kedip dan seberkas cahaya terang
melompat di depan mata Takeo. Sesaat
melayang-layang, kemudian melesat bak
bintang jatuh ke arah taman yang gelap.
Terdengar olehnya desisan cahaya tadi saat
hujan memadamkannya.
Di saat yang sama amarahnya lenyap.
"Gemba," ujar Takeo. "Aku senang ber-
temu denganmu! Tapi apakah kau meng-
habiskan waktu dengan belajar tipuan sulap
di sini?"
"Kaisar dan istananya sangat percaya
takhayul," sahut Gemba. "Mereka punya
banyak peramal, ahli nujum dan penyihir.
Bila aku menemanimu, kau mungkin bisa
yakin kalau kami mampu menandingi tipuan
mereka."
"Jadi aku harus pergi ke Miyako?"
"Ya," sahut Matsuda. "Kau harus hadapi
mereka sendiri. Kau akan mendapatkan
dukungan Kaisar."
"Aku akan membutuhkan lebih dari
sekadar tipuan Gemba untuk membujuknya.
Kaisar sedang membangun kekuatan untuk
melawanku. Aku takut kalau satu-satunya
jawaban yang masuk akal yaitu dengan
kekerasan."
"Sebentar lagi akan ada pertandingan ber-
taraf kecil di Miyako," ujar Gemba. "Itu
sebabnya aku harus ikut bersamamu. Putri-
mu juga harus ikut."
"Shigeko? Tidak, terlalu berbahaya."
"Kaisar harus bertemu dengannya dan
memberi restu serta persetujuan kepadanya
bila dia memang akan menjadi penerusmu
seperti yang seharusnya."
Seperti Gemba, Matsuda mengeluarkan
kata-kata ini dengan penuh keyakinan.
"Kita tidak perlu membahas hal ini?" tanya
Takeo. "Kita tidak perlu mempenimbangkan
pilihan Iain, dan mencapai kesimpulan yang
bijaksana?"
"Kita bisa membahasnya bila kau mau,"
sahut Matsuda. "Tapi aku sudah sampai pada
usia dimana perbincangan membuatku lelah.
Aku bisa lihat titik akhir yang akan dicapai.
Maka langsung saja ke bagian akhirnya."
"Aku juga harus meminta pendapat dan
saran istriku," ujar Takeo. "Begitu pula hal-
nya dengan para pengawal senior, dan
jenderalku, Kahei."
"Kahei akan selalu memilih perang," kata
Gemba. "Begitulah sifatnya. Tapi kau harus
menghindari bentrokan senjata secara ter-
buka, terutama bila prajurit dari wilayah
Timur mempunyai senjata api."
Kulit kepala dan leher Takeo terasa seperti
dihujam perasaan gelisah. "Kau yakin?"
"Tidak, aku hanya menduga kalau tak
lama lagi mereka akan memilikinya."
"Sekali lagi, ini ulah Zenko yang meng-
khianatiku."
"Takeo, sahabatku, bila kau memperkenal-
kan penemuan baru, baik itu senjata atau apa
saja, jika memang efektif, rahasianya akan
dicuri. Begitulah sifat manusia."
"Jadi seharusnya tidak kubiarkan pengem-
bangan senjata api?" Satu hal yang kerap
disesalinya.
"Begitu benda itu diperkenalkan padamu,
tak dapat dihindari kalau kau akan
mengembangkannya dalam pencarianmu
akan kekuatan dan kekuasan. Sama tidak ter-
hindarkannya ketika musuh-musuhmu
menggunakannya dalam usaha untuk men-
jatuhkan dirimu."
"Maka aku harus memiliki senjata api
yang lebih banyak dan lebih baik dibanding-
kan mereka! Aku harus serang mereka lebih
dulu, mengejutkan mereka, sebelum mereka
sempat mempersenjatai diri."
"Itu bisa menjadi strategi yang baik," kata
Matsuda mengamati.
"Tentu saja, adikku, Kahei, akan mem-
berimu saran seperti itu," timpal Gemba.
"Makoto," kata Takeo. "Kau diam saja.
Bagaimana pendapatmu?"
"Kau tahu aku tidak bisa menyarankanmu
memulai perang."
"Jadi kau takkan memberi saran? Kau akan
duduk di sini dan melantunkan doa serta
memainkan tipuanmu dengan api, sementara
semua yang sudah kuraih hancur
berantakan?" Bisa didengarnya nada suaranya
sendiri lalu ia diam seribu bahasa, setengah
merasa malu atas kekesalannya dan setengah
takut Gemba akan menggunakan api untuk
membuang amarahnya.
Kali ini tak ada unjuk kebolehan tipuan,
namun kesunyian yang makin dalam meng-
hasilkan efek yang sama kuatnya. Takeo me-
rasakan kombinasi antara ketenangan dun
kejernihan dari pikiran ketiga orang itu dan
tahu kalau mereka mendukungnya, namun
berusaha mencegahnya agar tidak bertindak
gegabah ataupun berbahaya. Banyak orang di
sekitarnya yang hanya bisa memuji dan
tunduk padanya. Sedangkan orang-orang ini
tidak melakukan itu, dan Takeo lebih
memercayai mereka.
"Bila aku harus ke Miyako, haruskah aku
pergi secepatnya? Saat musim gugur, saat
cuaca membaik?"
"Tahun depan, mungkin, saat salju sudah
mencair," tutur Matsuda. "Jangan terburu-
buru."
"Itu memberi mereka waktu untuk mem-
bangun kekuatan militer!"
"Itu juga memberimu waktu untuk
menyiapkan diri," sahut Makoto. "Kurasa
kau harus pergi dengan kemewahan yang
tiada tara, membawa hadiah-hadiah yang
paling indah."
"Juga memberi waktu pada putrimu untuk
menyiapkan dirinya," tutur Gemba.
"Tahun ini Shigeko berusia lima betas
tahun," ujar Takeo. "Dia sudah cukup
dewasa untuk ditunangkan."
Pikiran itu mengganggunya: baginya
Shigeko masih anak-anak. Siapa orang yang
pantas menjadi jodohnya?
"Itu juga menjadi nilai lebih di pihakmu,"
gumam Makoto.
"Sementara ini dia harus menyempurna-
kan keahlian berkuda, dan memanah," seru
Gemba.
"Dia takkan sempat menunjukkan semua
keahliannya di ibukota," kata Takeo.
"Kita lihat saja nanti," sahut Gemba, dan
tersenyum dengan ekspresi penuh teka-teki.
"Jangan khawatir," imbuhnya, seolah
memerhatikan rasa kesal Takeo. "Aku akan
ikut denganmu, dan takkan ada yang akan
menyakitinya."
Kemudian dia berkata dengan nada
bijaksana: "Putri-putri yang layak mendapat-
kan perhatianmu lebih dari putra-putra yang
tidak kau miliki."
Kata-kata itu terasa bagaikan hujaman
kritikan tajam dan menyengat, karena ia
mengagumi kenyataan bahwa dirnya men-
jalani semua pendidikan dan pelatihan bagi
anak laki-laki: Shigeko dengan cara ksatria, si
kembar dengan ketrampilan Tribe. Takeo
mengatupkan bibir lalu membungkuk
hormat di hadapan Matsuda. Orang itu
memberi isyarat untuk mendekat dan
merangkulkan tangannya yang lemah pada
Takeo. Ia tidak bicara sepatah ia pun, tapi
tiba-tiba ia sadar kalau Matsuda sedang
mengucapkan selamat tinggal, kalau ini
adalah pertemuan mereka yang terakhir.
Takeo mundur sedikit agar bisa menatap
dalam-dalam mata sang pendeta tua.
Matsuda adalah satu-satunya orang yang bisa
kutatap langsung wajahnya, pikirnya. Satu-
satunya orang yang tidak jatuh dalam sihir
tidur Kikuta.
Seolah bisa membaca pikirannya, Matsuda
berkata, "Aku tidak meninggalkan siapa-siapa
selain dua penerus yang berhargatak ter-
nilai harganya. Jangan membuang waktumu
dengan menyesali kepergianku. Kau sudah
tahu apa yang perlu kau ketahui. Berusahalah
mengingatnya."
Nada suaranya mengandung gabungan
antara kasih sayang dan amarah yang sering
digunakannya saat mengajari Takeo cara
menggunakan pedang. Sekali lagi Takeo
harus mengedipkan mata agar air matanya
tidak jatuh.
Sewaktu Makoto menemaninya ke griya
tamu, sang biarawan berkata, "Kau ingat saat
pergi seorang diri ke sarang perompak di
Oshima? Miyako tidak mungkin lebih ber-
bahaya dari tempat itu!"
"Kala itu aku masih muda dan tanpa rasa
takut. Aku tak percaya ada orang yang bisa
membunuhku. Kini aku sudah tua, cacat,
dan rasa takutku jauh lebih banyak bukan
hanya takut kehilangan nyawaku sendiri, tapi
juga nyawa anak-anakku, dan istriku, juga
negara dan rakyatku, bila aku mati, mereka
tanpa perlindungan."
"Itu sebabnya yang terbaik yaitu dengan
menunda jawabanmu: kirimkan pesan yang
penuh pujian, hadiah dan janji-janji. Kau
selalu bertindak tanpa berpikir: semua yang
kau lakukan dilakukan dengan tergesa-gesa."
"Itu karena aku sadar kalau aku tak akan
hidup lama. Hanya ada sedikit waktu untuk
meraih apa yang ingin kuraih."
***
Takeo tertidur sambil memikirkan tindakan-
nya yang hanya menuruti kata hati tanpa ber-
pikir panjang, dan bermimpi berada di
Yamagata, di malam ia memanjat ke kastil
lalu mengakhiri penderitaan kaum Hidden
yang disiksa. Dalam mimpinya, ia bergerak
lagi dengan kesabaran tanpa batas Tribe,
melewati malam yang terasa tanpa akhir.
Kenji mengajarinya cara membuat waktu
bergerak lambat atau mempercepatnya sesuai
keinginan. Dilihat dalam mimpinya bagai-
mana dunia berubah sesuai dengan harapan-
nya, dan terbangun dengan perasaan kalau
semacam misteri baru saja terangkat dari
dalam dirinya, tapi juga dengan semacam
kebahagiaan tiada tara, dan dengan anehnya
ia terbebas dari rasa sakit.
Saat itu hari hampir terang. Tak terdengar
rintik hujan, hanya kicau burung dan tetesan
sisa air hujan dari tepi atap. Sunaomi duduk
di atas matras sambil menatapnya.
"Paman? Paman sudah bangun? Bisakah
kita pergi dan melihat burung houou?"
Para pengawal Arai tetap berjaga
semalaman di luar, walaupun Takeo sudah
meyakinkan mereka kalau Sunaomi lak
dalam bahaya. Kini mereka berdiri setengah
melompat, membantu tuan muda mereka
memakai sandal, lalu mengikuti sewaktu
Takeo membimbingnya berjalan ke gerbang
utama. Palang gerbang sudah dibuka sejak
matahari terbit dan sudah ditinggalkan
penjaganya untuk sarapan. Setelah melewati
gerbang itu, mereka berbelok ke kanan dan
mengambil jalan sempit menuju dinding
sebelah luar dari dataran biara dan berjalan
naik ke lereng gunung yang curam.
Tanahnya keras dan berbatu, kerap terasa
licin karena hujan. Setelah beberapa saat,
salah seorang pengawal menggendong
Sunaomi. Langit tampak cerah, biru pucat,
matahari baru saja terbit di timur
pegunungan. Jalannya menanjak dan menuju
hutan pohon beech dan pohon ek. Hamparan
bunga liar musim panas menyelimuti per-
mukaan tanah, dan burung melantunkan
nyanyian dengan saling bersahutan. Nanti
udara akan terasa panas, tapi kini udara
terasa sempurna, didinginkan hujan, dan
tenang.
Takeo bisa mendengar gemerisik de-
daunan dan kepakan sayap yang menunjuk-
kan keberadaan burung houou di dalam
hutan di depan sana. Di sini, di antara
pepohonan berdaun lebar, terdapat sebuah
rumput ilalang tinggi yang menjadi tempat
yang paling disukai burung-burung itu untuk
bersarang dan bertelur, walaupun kabarnya
mereka makan daun bambu.
Kini jalannya lebih mudah dilewati,
Sunaomi meminta agar diturunkan, dan yang
membuat Takeo terkejut, anak itu
memerintahkan kedua orang itu menunggu
di sini sementara dia berjalan ke depan ber-
sama Lord Otori.
Sewaktu mereka sudah berada di luar
jangkauan pendengaran kedua pengawal itu,
Sunaomi berkata dengan nada penuh rahasia
pada Takeo, "Aku pikir Tanaka dan Suzuki
tidak perlu melihat burung houou. Mungkin
saja mereka ingin memburu atau mencuri
telurnya. Aku pemah mendengar kalau telur
burung houou bernilai tinggi."
"Mungkin nalurimu benar," sahut Takeo.
"Mereka tidak seperti Lord Gemba dan
Lord Makoto," ujar Sunaomi. "Aku tidak
tahu cara mengungkapkannya. Kedua
pengawal itu bisa melihat, tapi takkan
mengerti."
"Kau mengutarakannya dengan sangat
baik," sahut Takeo sambil tersenyum.
Kicau penuh semangat terdengar dari atas
kepala mereka, diikuti oleh jeritan parau
sebagai jawabannya.
"Itu mereka," bisik Takeo, seperti biasa
rasa kagum pada burung suci itu bangkit
dalam dirinya. Seruan mereka seperti juga
kehadiran mereka, indah serta aneh, anggun
juga canggung. Burung-burung itu memang
memberi semangat sekaligus agak lucu. Ia
takkan terbiasa dengan kehadiran mereka.
Sunaomi mendongak, wajahnya tampak
terpesona. Lalu seekor burung melesat keluar
dari balik rimbunnya dedaunan dan me-
ngepakkan sayap ke pohon berikumya.
"Itu burung jantan," tutur Takeo. "Dan
ini dia yang betina."
Sunaomi tertawa gembira sewaktu burung
kedua terbang menukik melintasi padang
rumput, ekornya panjang dan halus, matanya
cemerlang bak kilauan emas. Bulunya
berwarna-warni, dan saat mendarat di dahan,
selembar melayang jatuh.
Kedua burung itu memalingkan kepala
saling berpandagan, berseru lagi, masing-
masing dengan suara yang khas melihat
sebentar tapi dengan tatapan tajam ke arah
kro, kemudian terbang menjauh ke dalam
hutan.
"Ah!" Sunaomi menahan napas lalu
mengejar mereka, menatap ke atas tanpa
memerhatikan jalan hingga dia jatuh di atas
rumput. Ketika berdiri, bulu itu berada di
tangannya.
"Lihat, Paman!"
Takeo menghampiri bocah itu kemudian
mengambil bulu itu. Matsuda pemah mem-
perlihatkan bulu burung houou, bersayap
putih. dengan ujung bulu warna merah. Bulu
itu berasal dari burung yang pernah dilihat
Shigeru ketika masih kecil, dan sejak saat itu
diawetkan di biara. Bulu yang ini berwarna
kuning keemasan gelap, selain dari batang
bulunya yang berwarna putih bersih.
"Simpanlah," katanya pada Sunaomi.
"Bulu itu akan mengingatkanmu pada hari
ini, dan anugerah yang kau peroleh. Inilah
sebabnya kami selalu mencari kedamaian,
agar burung houou tidak meninggalkan Tiga
Negara."
"Aku akan berikan bulu ini ke biara,"
sahut Sunaomi, "sebagai sumpah bahwa
kelak aku akan kembali dan belajar pada
Lord Gemba."
Anak ini baik hati, pikir Takeo. Aku akan
membesarkannya sebagai putraku.*
Setelah kepergian Takeo dan Sunaomi, Taku
duduk d beranda sambil menatap taman
yang basah kuyup tersiram hujan, memikir-
kan semua ucapan sepupu ibunya itu.
Masalah itu mengganggunya lebih dari yang
ia duga, karena hal itu dapat menjerumuskan
ia dalam konflik ter buka dengan kakaknya,
sesuatu yang ia berharap bisa dihindari.
Betapa bodohnya Zenko, pikirnya, dan sedari
dulu dia selalu begitu. Sama seperti ayah!
Di usia sepuluh tahun, sebelum gempa
mengguncang kota, ia menyaksikan ayahnya
mengkhianati Takeo. Zenko menyalahkan
Takeo atas kematian Arai, namun Taku me-
nafsirkan seluruh adegan itu dengan cara
yang berbeda. Ia tahu kalau ayahnya me-
merintahkan untuk membunuh ibunya: ia
tak bisa melupakan atau memaafkan niat
ayahnya untuk ia dan kakaknya. Taku
mengira Takeo akan membunuh Zenko
seringkali setelah kejadian itu ia bermimpi
kalau Takeo memang membunuhnyadan
tidak pernah bisa memahami kebencian
Zenko terhadap Takeo karena membiarkan-
nya tetap hidup.
Sejak kecil Taku memuja Takeo sebagai
pahlawan, dan sebagai laki-laki dewasa, ia
menghormati dan mengagumi Takeo. Ter-
lebih lagi, keluarga Muto telah bersumpah
pada keluarga Otori: ia tak akan melanggar
sumpah itu. Bila tidak terikat oleh kewajiban
pcnghormatan dan kesetiaan, ia pasti akan
sama bodohnya dengan Zenko: kedudukan
di Tiga Negara adalah segala yang diingin-
kanya, memberinya kekuasaan dan status
serta memungkinkan dirinya mengambil
banyak keuntungan dari semua bakatnya.
Takeo juga mengajarinya semua hal yang
pernah dia pelajari dari Kikuta. Taku
tersenyum pada dirinya sendiri, mengenang
seringkali tertidur terkena ilmu tidur Kikuta
sampai akhimya bisa menghindarinya
bahkan sampai ia pun mampu melakukan-
nya. Ada ikatan kuat antara mereka berdua;
mereka mirip dalam banyak hal, dan
keduanya memahami konflik akibat darah
campuran.
Namun, seorang kakak tetap saja kakak,
dan Taku dibesarkan untuk menghormati
hierarki Tribe. Ia mungkin siap membunuh
Zenko, seperti yang diucapkan pada Takeo,
tapi takkan menghina kakaknya dengan
mengabaikan haknya untuk mengajukan
pendapat siapa yang akan menjadi kepemim-
pinan keluarga Muto. Taku memutuskan
akan mengusulkan ibunya, Shizuka,
keponakan Kenji. Usulan ini mungkin bisa
diterima semua pihak.
Suami ibunya, tabib Ishida, akan mem-
bawa anak Zenko yang satu lagi ke Hagi. Ia
bisa membawa surat atau pesan lisan kepada
Shizuka. Ishida, menurut Taku, cukup bisa
dipercaya. Kelemahan utama laki-laki itu
terletak pada keluguannya, seolah dia sulit
memahami kekejian yang mungkin
terpendam dalam sifat manusia. Terlepas dari
keberanian yang dibutuhkan untuk bisa pergi
jauh dalam penjelajahannya, secara fisik,
Ishida bukan seorang pemberani, dan tidak
suka bertarung.
Taku sendiri akan tetap berada di dekat
Zenko dan Kono, bahkan mungkin melaku-
kan perjalanan bersama Kono ke wilayah
Barat, tempat ia akan mengatur pertemuan
dengan Sugita Hiroshi, teman lamanya.
Penting bagi Kono mendapat gambaran Tiga
Negara yang sebenarnya untuk dibawa
pulang ke ibukota, menjelaskannya kepada
Kaisar bahwa Lord Otori didukung penuh di
Maruyama dan Inuyama, sedangkan Zenko
berdiri sendiri.
Cukup puas dengan keputusan ini, Taku
pergi ke istal untuk melihat keadaan si kuda
tua, Ryume, yang sudah pulih dari kelelahan
karena perjalanan jauh. la senang dengan apa
yang ditemukannya di sana: apa pun kesa-
lahan kakaknya, pengetahuan dan kepeduli-
annya pada kuda tak ada tandingannya.
Ryume sudah dibersihkan: surai dan ekornya
dibersihkan dari lumpur dan tak lagi kusut;
kuda itu diberi makan cukup dan kelihatan
senang. Meskipun sudah tua, Ryume masih
tetap kuda yang baik, dan perawat kuda
mengaguminya secara terang-terangan, bah-
kan memperlakukan Taku dengan rasa hor-
mat yang lebih besar lagi.
Taku masih mengelus-elus dan memberi-
nya makan wortel sewaktu Zenko datang ke
area istal. Mereka saling menyapa dengan
penuh kehangatan, karena masih ada sisa-sisa
kasih sayang di antara mereka, ikatan dari
masa kanak-kanak yang sejauh ini bisa
mencegah keretakan hubungan mereka.
"Kau masih memiliki anak Raku," ujar
Zenko, mengulurkan tangan dan meng-
gosok-gosok alis si kuda. Taku ingat pada
rasa iri Zenko ketika mereka kembali ke Hagi
pada musim semi bersama dua kuda jantan
yang tampan, satu milik Hiroshi dan satu
lagi miliknya, indikasi jelas kasih sayang
Takeo pada mereka berdua, hanya semakin
menekankan sikap dinginnya terhadap
Zenko.
"Akan kuberikan kuda ini untukmu,"
ujarnya tanpa rpikir panjang. "Dia belum
terlalu tua untuk dikawinkan dan mendapat-
kan anak." Selain anak-anaknya, Taku tidak
bisa menawarkan sesuatu yang lebih berharga
lagi. Ia berharap kemurahan hatinya bisa
melembutkan perasaan Zenko terhadapnya.
"Terima kasih, tapi aku takkan menerima-
nya," sahut Zenko. "Ryume adalah hadiah
dari Lord Otori, lagipula kurasa dia sudah
terlalu tua untuk punya anak."
"Seperti Lord Otori," komentarnya se-
waktu mereka kembali ke kediaman, "yang
harus memiliki putra dari laki-laki yang lebih
muda."
Taku sadar kalau perkataan ini semestinya
hanyalah lelucon, tapi ada nada sinis di
dalamnya. Kakakku mengartikan segala se-
suatunya sebagai penghinaan, pikirnya.
"Sungguh kehormatan bagimu dan istri-
mu," katanya dengan ringan, tapi wajah
Zenko tampak murung.
"Benarkah suatu kehormatan, atau kini
mereka menjadi tawanan?" tanyanya.
"Itu tergantung padamu," sahut Taku.
Zenko menanggapi dengan jawaban yang
tidak tegas lalu mengalihkan topik pem-
bicaraan.
"Bukankah kau harus pergi ke rumah
keluarga Muto untuk upacara pemakaman?"
tanya Zenko sewaktu mereka duduk di
datam.
"Lord Takeo ingin mengadakan upacara di
Hagi. Ibu ada di sana, dan karena tak ada
jenazah yang bisa makamkan...."
"Tidak ada jenazah? Jadi Kenji mati di
mana? Dan bagaimana kita tahu kalau dia
memang sudah mati? Ini bukan pertama
kalinya dia menghilang demi kepentingan-
nya sendiri?"
"Aku yakin Paman sudah tiada." Taku
melihat kakaknya sekilas lalu melanjutkan
perkataannya, "Paman sakit parah: mungkin
meninggal akibat sakit paru-paru, tapi misi
yang sedang dilaksanakannya luar biasa ber-
bahaya, dan telah mengatur untuk kembali
secepatnya ke Inuyama jika berhasil. Aku
katakan ini padamu dengan penuh ke-
yakinan. Kabar resminya adalah: Paman
meninggal karena sakit paru-paru."
"Bukan mati di tangan Kikuta?" ujar
Zenko setelah terdiam lama.
"Mengapa kau berpikir begitu?"
"Aku mungkin saja memakai nama Ayah,
adikku, tapi itu tak mengubah kenyataan
kalau aku sama sepertimu, keluarga Tribe.
Aku punya orang dalam di kalangan Muto
dan di kalangan Kikuta. Semua orang tahu
kalau putra Akio adalah cucu Kenji. Pasti
Kenji sangat ingin bertemu dengannya
Kenji sudah tua, kesehatannya memburuk.
Akio, kabarnya, tidak pernah memaafkannya
dan juga Takeo atas kematian Kotaro. Aku
hanya menarik kesimpulan dari fakta yang
ada. Aku harus melakukannya karena Takeo
tak memercayaiku seperti dia memercayai-
mu."
Taku merasakan kebencian dalam suara
kakaknya, tapi yang mengkhawatirkannya
dibandingkan komentamya bahwa dia me-
miliki orang dalam di kalangan Kikuta.
Benarkah itu, atau Zenko hanya membual?
Taku menanti dalam diam, melihat apa
lagi yang akan Zenko ungkapkan.
"Tentu saja ada desas-desus di desa Muto
mengenai anak itu," lanjut Zenko. "Bahwa
Takeo adalah ayahnya, bukan Akio." Zenko
berkata dengan santai, tapi Taku tahu betul
minat mendalam di balik kata-kata itu.
"Hanya Muto Yuki yang tahu pasti," sahut
Taku. "Dan dia meninggal tak lama setelah
anak itu lahir."
"Ya, aku ingat," kata Zenko. "Baiklah,
siapa pun ayahnya, anak itu adalah cucu
Kenji, dan keluarga Muto memiliki kepen-
tingan padanya. Bila aku menjadi Ketua, aku
akan menghubungi Kikuta berkaitan dengan
anak itu."
"Mungkin sebaiknya kita biarkan saja
pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi
penerus Kenji sampai kita membicarakannya
dengan ibu," sahut Taku sopan. "Aku ngak
terkejut bila harus mengingatkanmu bahwa
Ketua keluarga biasanya memiliki kemampu-
an tinggi."
Kemarahan Zenko mulai meluap, matanya
menyipit. "Aku memiliki banyak kemampu-
an Tribe, adikku. Kemampuan-kemampuan
itu mungkin tidak semenyolok kemampuan
yang kau miliki, tapi sangat efektifl!
Taku agak menundukdengan tidak
tulusagar kelihatan patuh, lalu mereka ber-
ganti topik pembicaraan yang lebih aman.
Tak lama kemudian Lord Kono datang
bergabung; menyantap makan siang bersama
kemudian pergi bersama Hana dan kedua
putranya untuk melihat kirin. Setelah itu
tabib Ishida diundang ke kediaman agar bisa
lebih akrab dengan Chikara sebelum meng-
ajaknya pergi ke Hagi.
Ishida tampak sangat gugup bertemu
Kono, dan bahkan lebih tegang lagi sewaktu
sang bangsawan bertanya tentang waktu yang
pernah dilewatkannya di kediaman Lord
Fujiwara. Ishida menerima undangan itu
dengan enggan, dan datang agak terlambat
saat makan malam, dalam keadaan agak
mabuk.
Taku sendiri merasa tegang, gelisah me-
mikirkan pembicaraannya dengan Zenko dan
sadar akan semua perasaan terpendam di
ruangan itu selama mereka makan. Sesuai
kebiasaannya, Taku tidak memperlihatkan-
nya, ia berbincang ringan dengan Kono,
memuji Hana atas hidangannya dan kedua
putranya serta berusaha menarik Ishida ke
topik pembicaraan yang tidak menyinggung,
seperti adat istiadat orang-orang nomaden
atau siklus hidup ikan paus. Hubungan Taku
dengan kakak iparnya agak menyakitkan
hati. Taku tidak terlalu suka ataupun percaya
pada Hana tapi perempuan itu punya
kecerdasan dan semangat yang tak pernah
berhenti dikaguminyadan tak ada laki-laki
yang tidak terpesona oleh kecantikannya.
Kini Taku ingat bagaimana mereka semua
terpesona olehnya saat masih anak-anak-dia,
Zenko dan Hiroshi. Mereka semua mem-
buntutinya ke mana pun Hana pergi bak
anjing dengan lidah terjulur keluar, dan
saling bersaing untuk merebut perhatian
gadis itu.
Sudah menjadi rahasia umum kalau ayah
Kono lebih suka berhubungan dengan laki-
laki ketimbang perempuan, tapi Taku tak
melihat apa pun yang menunjukkan ke-
miripan sifat Kono dengan ayahnya. Taku
seperti melihat ketertarikan yang cukup
alami di balik perhatian Kono pada Hana.
Mustahil bila tidak berhasrat pada Hana,
pikirnya. dan pikirannya melayang mem-
bayangkan bagaimana rasanya terbangun
dalam kegelapan dengan perempuan itu di
sisinya. Hampir saja ia iri pada Zenko.
"Tabib Ishidalah yang merawat ayah
Anda," komentar Hana pada Kono. "Dan
sekarang dia merawat kesehatan Lord Otori."
Taku mendengar nada mendua hati
sekaligus kedengkian dalam suaranya, dan
hasratnya berubah menjadi rasa tidak suka. Ia
bersyukur telah pulih dari perasaan tergila-
gila pada perempuan itudan tidak pernah
merasakannya lagi. Ia langsung berpikir
tentang istrinya sendiri, yang ia tahu bisa
dipercaya dan dirindukannya. Musim panas
kali ini akan berlangsung lama, dan melelah-
kan.
"Dengan keberhasilan yang gemilang,"
sambung Zenko, "Tabib Ishida sudah sangat
sering menyelamatkan Lord Otori dari
kematian."
"Ayahku selalu menghargai kemampuan
Anda," ujar Kono pada Ishida.
"Anda terialu berlebihan menyanjungku.
Kemampuanku biasa saja."
Taku mengira Ishida takkan berkomentar
lebih banyak lagi tentang masalah ini, namun
setelah menenggak habis sake sekali lagi, si
tabib melanjutkan perkataannya, "Tentu saja
kasus Lord Otori cukup mengagumkan, dari
sudut pandang seorang laki-laki seperti diriku
yang tertarik pada bagaimana cara manusia
berpikir." Dia berhemi sejenak, kemudian
membungkuk dan berkata dengan nada
penuh rahasia. "Lord Otori percaya tak ada
yang bisa membunuh dirinyadia telah
membuat dirinya kekal."
"Bcnarkah?" gumam Kono. "Kedengaran-
nya terlalu pongah. Apakah itu semacam
takhayul?"
"Kurang lebih begitu. Dan sangat berguna.
Ada semacam ramalanTaku, kau ada di
sana ketika pamanmu yang malang"
"Aku tidak ingat," sahut Taku cepat.
"Chikara, bagaimana perasaanmu tentang
perjalanan lewat laut bersama kirin?"
Chikara menelan ludah saat diajak bicara
pamannya, dan belum sempat dia menyahut,
Zenko lalu bertanya, "Ramalan apa?"
"Bahwa Lord Otori hanya bisa mati di
tangan putranya." Ishida minum lagi.
"Mengapa aku membicarakan hal itu? Oh ya,
efek dari kuatnya kepercayaan itu berimbas
pada tubuhnya. Dia percaya tidak bisa di-
bunuh, dan tubuhnya bereaksi dengan
sembuh dengan sendirinya."
"Mengagumkan," sahut Kono dengan
sikap halus. "Lord Otori memang berhasil
luput dari banyak serangan atas dirinya.
Pernahkah kau tahu kasus-kasus serupa?"
"Tentu aku tahu," sahut Ishida. "Dalam
perjalanan ke Tenjiku, di sana ada orang-
orang suci yang bisa berjalan di atas api tanpa
terbakar, serta berbaring di atas ranjang
berpaku tanpa melukai kulit mereka."
"Kau tahu hal ini, adikku?" tanya Zenko
pelan, sementara Kono mendesak Ishida
menceritakan lebih banyak banyak lagi ten-
tang perjalanan-perjalanannya.
"Itu tidak lebih dari kepercayaan
takhayul," sahut Taku ringan, dalam hati
berharap segala siksaan neraka menimpa si
tabib yang sedang mabuk. "Keluarga Otori
merupakan sasaran desas-desus."
"Kakakku, Kaede, pernah menjadi sasaran
desas-desus semacam itu," timpal Hana. "Dia
seharusnya membawa kematian pada laki-laki
manapun yang menginginkan dirinya, tapi
Lord Takeo terhindar dari bahaya itu.
Syukur dipanjatkan pada Surga," imbuhnya,
seraya melirik ke arah Taku.
Tawa yang mengikuti kata-kata Hana
selanjutnya terdengar agak kurang nyaman,
karena lebih dari satu orang yang hadir di
sana mengingat kalau Lord Fujiwara me-
nikahi lain Kaede secara paksa hingga
bangsawan itu mati.
"Tapi semua orang tahu tentang Lima
Pertempuran," lanjut Zenko. "Dan gempa
bumi'Bumi menghantarkan apa yang
diinginkan Surga.'" Dilihatnya wajah Kono
yang penuh tanda tanya lalu menjelaskan,
"Ada ramalan seorang perempuan suci, yang
dipastikan oleh kemenangan Takeo dalam
perang. Gempa bumi itu di percaya sebagai
pertanda dari Surga, yang berpihak kepada-
nya."
"Ya, begitulah yang aku dengar," sahut
Kono, dengan nada mengejek. "Alangkah
enaknya bagi sebuah kemenangan memiliki
ramalan yang berguna." Dia minum lalu
bicara dengan lebih serius, "Di ibukota
gempa bumi biasanya dianggap sebagai
hukuman atas tindak kejahatan, bukan
anugerah."
Taku tidak tahu apakah harus bicara dan
memberi tahu Kono di mana kesetiaannya
berpihak, atau diam saja dan kelihatan men-
dukung kakaknya. Ishida menyelamatkannya
yang bicara dengan perasaan yang meluap-
luap. "Gempa itu menyelamatkan nyawaku.
Dan nyawa istriku. Menurutku, kejahatan
telah mendapatkan balasannya."
Air matanya mengambang, lalu diseka
dengan lengan baju. "Maaf, aku tak ber-
maksud menghina kenangan tentang kedua
ayah kalian." Lalu dia berpaling ke arah
Hana. "Aku harus beristirahat. Aku lelah
sekali. Kuharap kalian memaafkan orang tua
ini."
"Tentu saja, Ayah," ujar Hana, bicara
padanya dengan sopan, karena Ishida adalah
ayah tiri suaminya. "Chikara, antar kakek ke
kamar dan minta pelayan membantunya."
"Aku khawatir dia sudah terlalu banyak
minum," Hana minta maaf pada Kono
setelah Chikara membantu si tabib berdiri
dan pergi.
"Ishida, laki-laki yang menarik. Aku
menyesal dia harus pergi ke Hagi. Kuharap
bisa berbincang banyak dengannya. Kurasa
dia lebih mengenal ayahku ketimbang orang
lain yang masih hidup."
Dan beruntung dia tidak mati seperti
ayahnya, pikir Taku.
"Ramalan yang menarik bukan?" tanya
Kono. "Kurasa, Lord Otori tidak memiliki
putra."
"Beliau memiliki tiga putri," sahut Taku.
Zenko tertawa, ledakan tawa yang me-
ngandung konspirasi jahat. "Secara resmi,"
tambahnya. "Ada lagi desas-desus tentang
Takeo... tapi aku harus bertindak bijak!"
Kono menaikkan alisnya. "Wah, wah!"
komentarnya.
Paman, apa yang harus kulakukan tanpa
dirimu? pikir Taku.*
Miyoshi Kahei menemani Takeo ke Hagi
bersama putra sulungnya, Katsumori. Hagi
adalah kota kelahirannya, dan gembira bisa
bertemu dengan sanak saudaranya. Sebalik-
nya, Takeo tahu kalau ia membutuhkan
saran Kahei tentang cara terbaik menghadapi
ancaman yang makin besar dari ibukota,
Miyako. Dari Kaisar dan jenderalnya, bagai-
mana ia menghabiskan musim dingin untuk
mengadakan persiapan.
Sulit memikirkan tentang musim dingin
saat ini, di akhir musim hujan plum*, di
mana hawa panas masih lerjadi. Kecemasan
lain yang harus dipikirkan sebelum perang
adalah panen, wabah penyakit menular, dan
penyakit akibat cuaca panas, penyimpanan
cadangan air untuk berjaga-jaga kalau terjadi
kekeringan di akhir musim panas. Tapi
* Hujan plum adalah hujan yang terjadi saat musim buah
plum (Juni-Juli). Fenomena cuaca ini melanda pantai
timur Cina, melintasi Taiwan lalu ke timur sampai ke
selatan pasifik Jepang. Dalam bahasa Jepang discbut
meiyu dan baiu. [pent.]
semua masalah ini tak lagi terasa mendesak
sewaktu memikirkan kalau tak lama lagi ia
akan bertemu Kaede dan ketiga putrinya.
Mereka berkuda menyeberangi jembatan
batu di senja hari bermandikan rintik hujan
disertai cahaya matahari. Takeo sadar pakai-
annya terasa lembap: begitu sering pakaian-
nya basah kuyup sampai menempel di kulit
selama perjalanan hingga nyaris tidak ingat
bagaimana rasanya kering. Bahkan tempat
penginapannya pun terasa lembap, berbau
lembap dan jamur.
Di atas laut, langit cerah biru berubah
kuning di bagian barat saat matahari ter-
benam. Pegunungan di belakangnya tertutup
awan tebal, dan guntur bergemuruh sehingga
kuda-kuda terkejut dalam kelelahan.
Kuda tunggangannya udaklah istimewa; ia
merindukan kuda lamanya, Shun, dan
bertanya-tanya apakah bisa menemukan kuda
seperti itu. Ia akan bicara pada Mori Hiroki
tentang kuda, dan juga pada Shigeko. Bila
mereka harus berperang, maka akan dibutuh-
kan lebih banyak kuda... tapi ia tidak ingin
berperang.
Miyoshi bersaudara meninggalkannya di
depan gerbang. Turun dari kuda di dinding
luar utama kastil: kuda-kuda diiuntun pergi,
dan hanya mengajak Sunaomi, Takeo ber-
jalan melewati taman. Kabar sudah tersiar
lebih dulu ke kastil. Kaede menantinya di
beranda panjang yang mengelilingi ke-
diaman. Suara laut memenuhi udara, dan
seruan burung dara terdengar dari atap
rumah. Wajah Kaede bersinar gembira.
"Kami tak menduga kau kembali begitu
cepat! Kau berkuda dalam cuaca yang begitu
buruk! Kau pasti kelelahan. Dan basah
kuyup."
Indahnya hardikan sayang istrinya mem-
bangkitkan perasaan begitu kuat dalam diri
Takeo hingga sesaat ingin berdiri di sana
untuk selamanya. Lalu perasaan itu berganti
dengan hasrat untuk memeluknya, melarut-
kan diri dalam dekapannya. Namun kabar
pertama harus segera disampaikan, pada
Kaede, pada Shizuka.
Shigeko berlari menghampiri dari dalam
kediaman. "Ayah!" pekiknya, lalu berlutut
untuk melepaskan sandal lakeo. Kemudian
dia melihat Sunaomi yang tengah berdiri
malu-malu di belakang.
"Benarkah ini sepupu kami?" tanyanya.
"Ya, Sunaomi akan tinggal bersama kita
selama beberapa waktu."
"Sunaomi!" seru Kaede. "Tapi kenapa?
Apakah ibunya baik-baik saja? Apakah ada
sesuatu terjadi pada Hana?"
Takeo melihat kecemasan Kaede dan ber-
tanya-tanya seberapa banyak yang dapat ia
ceritakan tentang kecurigaannya.
"Hana baik-baik saja," sahut Takeo.
"Nanti kuceritakan alasan kunjungan
Sunaomi."
"Tentu saja. Ayo masuk. Kau harus segera
mandi, dan mengganti pakaian yang kering.
Lord Takeo, kau pikir masih berusia delapan
betas tahun? Kau sama sekali tak memikirkan
kesehatanmu!"
"Shizuka ada di sini?" tanyanya saat Kaede
membimbingnya di beranda menuju bela-
kang kediaman, tempat sebuah kolam dibuat
di sekeliling mata air panas.
"Ya, apa yang terjadi?" Kaede mendongak
sekilas ke wajah Takeo lalu berkata, "Shi-
geko, katakan pada Shizuka untuk segera me-
nemui kami. Minta pelayan untuk mem-
bawakan pakaian untuk ayahmu."
Wajah Shigeko tampak serius selagi mem-
bungkuk normal lalu meninggalkan mereka.
Takeo bisa mendengar langkah ringan putri-
nya di lantai papan; terdengar olehnya
Shigeko bicara pada kedua adiknya. "Ya,
ayah sudah pulang. Tapi kalian belum boleh
menemuinya. Ayo ikut aku. Kita harus me-
nemukan Shizuka."
Mereka hanya berdua. Sinar matahari
keluar dari sela-sela bunga-bunga dan semak-
semak. Di sekeliling kolam dan sungai,
bunga iris tampak berkilauan. Langit dan
laut berbaur menjadi satu dalam kabut senja.
Satu demi satu api dan lentera di sekitar
teluk mulai dinyalakan dalam kegelapan.
Kaede tidak bicara sepatah kata pun sewaktu
melepaskan pakaian Takeo.
"Muto Kenji sudah tiada," kata Takeo.
Kaede mengambil air dari kolam dengan
ember bambu dan mulai memandikan
suaminya. Takeo melihat air mata meng-
genang di mata istrinya lalu mulai berlinang
di pipinya. Sentuhannya menenangkan. Tiap
jengkal tubuhnya terasa sakit. Takeo ingin
Kaede melingkarkan tangan lalu memeluk-
nya, tapi ia harus bicara dulu pada Shizuka.
Kaede berkata, "Suatu kehilangan yang
menyakitkan. Bagaimana kejadiannya? Apa-
kah dia meninggal karena sakit?"
Takeo mendengar dirinya berkata, "Se-
pertinya begitu. Dia mengadakan perjalanan
sampai keluar perbatasan. Tak ada kabar
yang jelas. Taku mengabarkan hal ini padaku
di Hofu."
Ia tidak berlama-lama di dalam air panas
seperti yang ia inginkan, dan segera keluar
dan berpakaian secepatnya.
"Aku harus bicara berdua dengan
Shizuka."
"Tentunya tak ada yang kau rahasiakan
padaku?"
"Hanya masalah Tribe," sahutnya. "Kenji
adalah Ketua Muto. Shizuka harus memilih
penggantinya. Hal ini tak bisa dibicarakan
dengan orang luar."
Dilihatnya kalau Kaede tidak senang,
kalau istrinya masih ingin bersamanya.
"Ada banyak hal lain yang perlu kita
bicarakan," tutur Takeo untuk meredam
kemarahan Kaede. "Saat kita hanya berdua,
aku akan menceritakan tentang Sunaomi,
dan kunjungan putra Lord Fujiwara..."
"Baiklah, Lord Takeo. Akan kusiapkan
makan untukmu," sahut Kaede lalu mening-
galkannya.
Ketika Takeo kembali ke ruang utama,
Shizuka sudah ada di sana. Takeo langsung
bicara tanpa salam lebih dulu. "Kau tentu
sudah bisa menduga kenapa aku di sini. Aku
pulang membawa kabar bahwa pamanmu
telah tiada. Taku datang ke Hofu untuk
mengabarkannya, dan kukira kau harus
segera tahu."
"Kabar seperti itu tidak pernah disambut
baik," sahut Shizuka dengan nada resmi,
"tapi bukannya tidak diharapkan. Terima
kasih, sepupu, atas keprihatinanmu, atas
sikapmu menghormati pamanku."
"Kurasa kau sudah tahu seberapa besar arti
Kenji bagiku. Tak ada jenazah, tapi kita akan
menghormatinya dengan mengadakan upa-
cara di sini atau di Yamagata, di mana pun
menurutmu yang paling sesuai."
"Kukira kemungkinan paman meninggal
di Inuyama," sahutnya perlahan. "Paman
tinggal di sana, kan?"
Tak seorang pun tahu misi yang dilakukan
Kenji kecuali ia dan Taku. Kini Takeo
menyesal mengapa tidak memberitahu
Shizuka sebelumnya. "Mendekatlah," kata-
nya. "Aku harus ceritakan semua yang aku
tahu karena hal itu memengaruhi Tribe."
Belum sempat Shizuka bergerak men-
dekat, seorang pelayan datang membawa teh.
Shizuka menuangkannya untuk Takeo.
Selagi Takeo minum, Shizuka bangkit, me-
lihat ke sekeliling ruangan dengan cepat,
membuka pintu lemari, kemudian melang-
kah ke beranda dan mengintip di bawahnya.
Dia kembali dan duduk di hadapan
Takeo, lutut mereka saling berhadapan.
"Apakah kau dengar ada orang di dekat sini?"
Takeo memasang telinga, "Tidak, tidak
ada orang lain."
"Kedua putrimu mulai mahir menguping,
dan bisa bersembunyi di tempat yang paling
sempit sekalipun."
"Terima kasih. Aku tak ingin putriku atau
istriku mendengar pembicaraan kita. Kukata-
kan pada Kaede kalau Kenji meninggal
karena penyakit; kalau Kenji mencari obat
sampai keluar perbatasan wilayah Timur."
"Dan yang sebenarnya?"
"Kenji pergi berunding dengan Kikuta.
Setelah peristiwa di Inuyama, kami pikir bisa
memanfaatkan anak-anak Gosaburo untuk
menekan mereka agar mau berdamai." Takeo
menghela napas, lalu melanjutkan bicara.
"Kenji ingin bertemu anak Yuki, cucunya.
Taku hanya tahu kalau Yuki meninggal di
desa Kikuta tempat Akio dan anak itu
bersembunyi selama beberapa tahun ini."
"Takeo, kau harus ceritakan semua ini
pada Kaede..."
Tidak dibiarkannya Shizuka melanjutkan
kata-katanya. "Ini kuceritakan karena me-
nyangkut masalah keluarga Muto yang kini
menjadikanmu anggota yang dituakan.
Kaede atau orang lain di luar Tribe tidak
perlu tahu."
"Lebih baik dia mendengar tentang anak-
mu itu dari mulutmu ketimbang dari orang
lain," sahut Shizuka.
"Aku sudah menyimpannya rapat-rapat
begitu lama hingga tak tahu bagaimana
memberitahukannya. Semua tudah berlalu:
anak itu putra Akio; putriku adalah pewaris-
ku. Untuk saat ini, ada pertanyaan mengenai
keluarga Muto dan Tribe. Kenji dan Taku
bekerjasama dengan baik: ilmu dan
ketrampilan yang Kenji miliki tak ada
bandingnya. Taku memiliki kemampuan
yang hebat, tapi kurasa kau sependapat kalau
ada semacam kegoyahan dalam dirinya: aku
ragu apakah dia cukup dewasa untuk me-
mimpin Tribe. Zenko adalah putra sulung-
mu, dan pewaris langsung Kenji, dan aku tak
ingin menghina atau mengganggunya, atau
memberinya dalih untuk..." Takeo berhenti
bicara.
"Untuk apa?" Shizuka menyela.
"Baiklah, kurasa kau tahu betapa mirip
sifat putramu dengan ayahnya. Aku khawatir
dengan niatnya. Aku tidak bermaksud mem-
biarkannya mengembalikan kita dalam
perang saudara lagi." Takeo bicara dengan
nada serius, lalu tersenyum dan meneruskan
dengan nada lebih ringan. "Maka aku meng-
atur agar kedua putranya menghabiskan
waktu bersama kita. Kurasa kau ingin ber-
temu cucumu."
"Aku sudah bertemu Sunaomi," tutur
Shizuka. "Tentu saja ini sangat menyenang-
kan. Apakah Chikara juga akan datang?"
"Suamimu akan membawanya dengan
kapal, bersama makhluk luar biasa yang dia
disebut kirin," sahut Takeo.
"Ah, Ishida sudah kembali; aku senang
mendengarnya. Kukatakan yang sebenarnya,
Takeo, aku sudah senang dengan hidupku
yang tenang, mendampingi Kaede dan anak-
anakmu, istri dari tabibmu...tapi rasanya kau
hendak membuat tuntutan lain padaku."
"Kau masih cepat tanggap seperti biasa,"
sahut Takeo. "ingin kau menjadi pemimpin
Muto. Taku akan bekerjasama denganmu
seperti yang dia lakukan bersama Kenji, dan
Zenko tentu akan tunduk padamu."
"Pemimpin keluarga disebut Ketua,"
Shizuka mengingatkan. "Dan belum pernah
ada Ketua perempuan!" tambahnya.
"Kau bisa menyebutnya apa saja. Itu akan
menjadi contoh yang baik. Aku hendak
memperkenalkannya ke wilayah lokal juga:
kita akan memulai dengan Negara Tengah
lalu kita sebarkan ke luar. Sudah banyak area
di mana perempuan dengan kebaikan dan
kemampuan dapat menggantikan posisi
suaminya. Mereka akan diakui dan diberi
wewenang yang sama seperti laki-laki."
"Jadi kau akan memperkuat negara ini dari
akar, dan para ksatria akan mendukung
putrimu?"
"Bila Shigeko menjadi satu-satunya
penguasa perempuan, dia juga harus bersikap
layaknya laki-laki. Bila perempuan lain
berada di puncak kekuasaan, kita mungkin
bisa melihat perubahan mengalir ke seluruh
Tiga Negara."
"Kau masih saja senang berkhayal,
sepupuku!" sahut Shizuka seraya tersenyum,
terlepas dari penderitaan yang ditanggung-
nya.
"Kau mau melakukannya, kan?"
"Baiklah, sebagian karena pamanku
pernah mengisyaratkan bahwa hal ini juga
keinginannya. Dan setidaknya sampai Taku
mantap dan Zenko sadar. Kurasa dia akan
sadar, Takeo, dan terima kasih atas tindakan-
mu yang berhati-hati padanya. Namun apa
pun hasilnya nanti, keluarga Muto akan tetap
setia padamu dan keluargamu." Shizuka
membungkuk hormat dengan sikap resmi.
"Aku bersumpah padamu sekarang, Lord
Otori, sebagai pemimpim mereka."
"Aku tahu apa yang telah kau lakukan
untuk Lord Shigeru dan keluarga Otori. Aku
berhutang banyak padamu," ujar Takeo
dengan penuh perasaan.
"Aku senang kita bisa bicara berdua,"
imbuh Shizuka, "karena kita harus mem-
bicarakan tentang si kembar. Aku berharap
bisa bertanya pada pamanku mengenai se-
suatu yang baru saja terjadi, tapi mungkin
kau tahu cara mengatasinya."
Diceritakannya pada Takeo mengenai
peristiwa yang terjadi pada kucing, bagai-
mana kucing itu tertidur dan tak pernah
bangun lagi.
"Aku tahu Maya memiliki kemampuan
ini," tutur Shizuka, "karena dia pemah mem-
perlihatkan tanda-tandanya selama musim
semi. Satu atau dua kali aku bahkan pusing
ketika dia menatapku. Tapi tak seorang pun
dari keluarga Muto tahu tentang sihir tidur
Kikuta, meskipun banyak takhayul yang ber-
kaitan dengan hal itu."
"Kemampuan itu seperti obat yang sangat
mujarab," sahut Takeo. "Sedikit akan
menguntungkan, tapi jika terlalu banyak
justru bisa menyebabkan kematian. Orang
membuat diri mereka terbuka pada kemam-
puan itu karena kelemahan diri mereka
sendiri, karena kurangnya pengendalian diri
mereka. Aku diajarkan untuk mengendali-
kannya di Matsuedan di sana aku belajar
bahwa Kikuta tak pernah menatap langsung
anak-anak mereka karena seorang anak tidak
dapat melawan tatapan itu. Kurasa seekor
kucing kecil sama lemahnya. Aku belum
pernah mencobanya pada kucing, hanya pada
anjingdan aku sudah mahir melakukan-
nya."
"Kau belum pernah mendengar per-
pindahan antara orang yang sudah mati
dengan orang yang membuat mereka
tertidur?"
Pertanyaan itu membuat bulu kuduk
Takeo berdiri. Hujan mulai turun lagi, dan
kini gemuruhnya semakin keras di atap.
"Biasanya bukan sihir tidur yang mampu
membunuh," tuturnya dengan hati-hati.
"Digunakan hanya untuk melemahkan:
kematian pasti disebabkan oleh hal lain."
"Itu yang mereka ajarkan padamu?"
"Mengapa kau menanyakan hal ini?"
"Aku mencemaskan Maya. Dia menunjuk-
kan tanda-tanda kerasukan. Ini pernah ter-
jadi di keluarga Muto, kau tahu; Kenji
dijuluki Si Rubah saat masih muda: kabarnya
dia pernah kerasukan roh rubahbahkan
menikah dengan seekor rubahtapi selain
pamanku, aku tidak tahu ada perubahan
bentuk yang pernah terjadi. Hampir seolah
Maya yang menarik roh kucing itu masuk ke
dalam dirinya. Semua anak suka bertingkah
seperti hewan, tapi seharusnya mereka lebih
manusiawi ketika mulai dewasa; Maya justru
sebaliknya. Aku tidak membicarakan hal ini
pada Kaede; Shigeko sudah curiga ada yang
tidak beres. Aku senang kau sudah kembali."
Takeo mengangguk, merasa gelisah
dengan kabar ini. "Cucu-cucumu tidak me-
nunjukkan tanda-tanda ketrampilan Tribe,"
komentarnya.
"idak, dan aku cukup lega. Biarlah mereka
menjadi putra Zenko, ksatria. Kenji
mengatakan bahwa kemampuan itu akan
menghilang dalam dua generasi. Mungkin,
dalam diri si kembar kita menyaksikan
pancaran sinar yang terakhir sebelum lentera-
nya padam."
Pancaran sinar yang terakhir ini bisa mem-
buat bayangan-bayangan aneh, pikir Takeo.
***
Tak seorang pun mengganggu selama mereka
berbincang-bincang: setengah sadar ia seperti
mendengar ada tarikan napas, bunyi
sambungan papan yang bergerak, langkah
ringan yang menandakan ada yang
menguping. Tapi saat memerhatikan lagi,
yang terdengar hanyalah siraman air hujan,
halilintar di kejauhan, dan hempasan ombak.
Namun ketika mereka selesai, dan Takeo
berjalan ke kamar Kaede di koridor yang
mengkilap, ia mendengar suara luar biasa di
depannya, semacam raungan dan geraman,
setengah manusia dan setengah hewan.
Kemudian terdengar suara memekik ke-
takutan, dan derap langkah kaki. Takeo ber-
belok di sudut dan Sunaomi menabrak-nya.
"Paman! Maaf!" Bocah itu tertawa
cekikikan kegirangan. "Macan itu ingin me-
nangkapku!"
Awalnya Takeo melihat bayangan di kertas
kasa. Sesaat terlihat jelas olehnya sosok tubuh
manusia, dan satu sosok lagi di belakangnya
dengan telinga rata, kuku yang siap mencakar
dan kibaskan ekor. Lalu si kembar datang
berlarian dari sudut, dan mereka berdua
hanyalah anak perempuan biasa, bahkan saat
sedang menggeram. Mereka langsung ber-
henti mematung ketika melihat ayahnya.
"Ayah!"
"Itu dia macannya!" jerit Sunaomi.
Miki melihat wajah ayahnya, menarik
lengan baju Maya lalu berkata, "Kami cuma
main-main."
"Kalian sudah terlalu besar untuk per-
mainan seperti itu," ujarnya, menyembunyi-
kan kekhawatirannya. "Bukan begini caranya
menyambut ayah kalian. Ayah berharap me-
nemukan kalian tumbuh menjadi perempuan
muda."
Seperti biasa, rasa tidak senang sang ayah
menciutkan nyali mereka.
"Maaf," kata Miki.
"Maafkan kami, Ayah," ujar Maya me-
mohon, tanpa sedikit pun sisa geraman
macan dalam suaranya.
"Ini salahku juga," imbuh Sunaomi.
"Semestinya aku sudah tahu. Lagipula,
mereka hanyalah anak perempuan."
"Ayah tampaknya perlu bicara serius
dengan kalian berdua. Di mana ibu kalian?"
"Ibu sedang menunggu Ayah. Kata ibu
mungkin kami boleh makan bersama Ayah,"
bisik Miki.
"Baiklah, Ayah kira kita harus menyambut
kedatangan Sunaomi. Kalian boleh makan
bersama kami. Tapi tidak ada lagi permainan
berubah menjadi macan!"
"Tapi manusia seharusnya mengumpan-
kan diri mereka pada macan," ujar Maya
selagi mereka berjalan di sampingnya.
"Shigeko yang menceritakan itu pada kami."
Maya tidak bisa menahan untuk berbisik
pada Sunaomi, "Dan yang paling disukai
macan adalah anak laki-laki."
Merasa jera atas teguran pamannya,
Sunaomi tidak menyahut.
Takeo bermaksud untuk berbicara dengan
si kembar malam ini, tapi seusai makan
malam, ia merasa kelelahan dan keinginan
berdua saja dengan Kaede. Kedua putri
kembarnya bersikap sempurna selama makan
malam, bersikap baik pada sepupu mereka,
dan sopan pada orangtua dan kakak sulung
mereka.
***
Saat ini Takeo menatap Kaede di bawah
keremangan cahaya lentera, tampak lekuk
tulang pipi dan siluet istrinya. Jubah tidur
membungkus tubuh Kaede yang duduk
bersila di matras, tubuh rampingnya tampak
putih samar-samar dengan selimut sutra.
Takeo berbaring dengan kepala di pangkuan
Kaede, merasakan panas tubuh istrinya,
mengenang dulu ia sering berbaring seperti
ini pada ibunya saat kecil. Rambutnya dibelai
lembut oleh Kaede sampai ke leher, me-
lemaskan syarafnya yang tegang.
Mereka hanyut dalam perasaan cinta, tak
lama setelah hanya berdua, nyaris tanpa kata-
kata, mencari kedekatan serta meleburkan
diri dalam kesatuan, senantiasa begitu akrab.
Mereka berbagi kesedihan atas kematian
Kenji tanpa suara, atau perasaan terasing dari
rahasia Takeo tentang Tribe atau pun
kekhawatiran tentang putri mereka. Semua
kecemasan ini kian membakar keintiman
tanpa kata-kata dari hasrat mereka dan
seperti biasa, ketika hasrat mereda, bak
mukjizat, pemulihan pun terjadi: sikap
dingin Kaede menguap; kesedihan Takeo
seperti bisa dilalui.
Banyak hal yang mesti dibicarakan.
Pertama tentang kecurigaan terhadap Zenko
dan alasan ia membawa kedua putra Arai ke
rumah mereka.
"Tentu kau takkan mengangkat mereka
secara sah menurut hukum, kan?" seru
Kaede.
"Bagaimana jika aku melakukannya?''
"Aku menganggap Sunaomi seperti anak
kandungkutapi Shigeko akan tetap
menjadi pewarismu?"
"Ada banyak kemungkinan: bahkan
pernikahan, saat dia cukup dewasa. Aku tak
ingin melakukannya dengan tergesa-gesa.
Semakin lama kita menunda keputusan,
semakin besar kemungkinan Zenko tersadar
dan tenang. Tapi aku khawatir dia didukung
Kaisar dan para pendukungnya di wilayah
Timur. Kita harus berterima kasih pada
penculikmu untuk hal itu!"
Diceritakannya tentang penemuannya
dengan Lord Kono. "Mereka mencap diriku
sebagai penjahat. Karena Fujiwara adalah
kerabat Kaisar sehingga dia terbebas dari
kejahatannya!"
"Kuatnya tekadmu soal sistem keadilan
mungkin telah membuat mereka ketakutan,"
kata Kaede. "Karena hingga saat ini tak
seorang pun berani mencela atau meng-
hukum orang seperti Fujiwara. Aku tahu dia
bisa saja membunuhku tanpa berpikir
panjang. Tak seorang pun berani menolak
perintahnya, tidak ada yang berpikir kalau
apa yang dilakukannya salah. Perasaan laki-
laki tidak lebih berharga dari sebuah lukisan
atau jambangan berhargakarena dia bisa
membunuh perempuan dengan entengnya
seolah hanya menghancurkan salah satu
hartanyaaku nyaris tidak bisa mengung-
kapkan dengan kata-kata betapa sikapnya
melemahkan keinginanku dan membuat
tubuhku serasa lumpuh. Kini pembunuhan
atas perempuan di Tiga Negara akan
dihukum sama seperti pembunuhan terhadap
laki-laki, dan tidak ada orang yang bisa lolos
dari keadilan hanya karena derajat mereka.
Keluarga-keluarga ksatria kita lelah me-
nerimanya, namun di luar perbatasan kita,
baik itu ksatria maupun bangsawan akan
menganggap hukum sebagai penghinaan.
"Kau mengingatkan betapa banyak hal
yang dipertaruhkan. Aku takkan mengun-
durkan diri seperti permintaan Kaisar, tapi
aku juga tak ingin terjadi peperangan.
Namun bila kita memang harus berperang di
wilayah Timur, maka makin cepat makin
baik." Takeo menceritakan tentang senjata
api, dan misi Fumio. Tentu saja Kahei
berpikir kita harus segera bersiap: kita punya
waktu untuk membangun kekuatan sebelum
musim dingin. Tapi di Terayama semua
Guru Besar menentangnya. Mereka mengata-
kan kalau aku harus pergi ke ibukota musim
semi depan bersama Shigeko, dan semua
masalah akan terpecahkan."
Takeo mengernyitkan dahi. Kaede meng-
gosokkan jari di dahi Takeo, menghaluskan
garis-garis kerutannya.
"Gemba memiliki serangkaian tipuan
baru," ujarnya. "Tapi kukira akan mem-
butuhkan lebih dari sekadar itu untuk
meredam nafsu kekuasaan jenderal Kaisar,
Saga Hideki, Si Pemburu Anjing."**
Keesokan harinya dilakukan persiapkan
upacara pemakaman Kenji, dan mendiktekan
surat-surat. Minoru dibuat sibuk seharian,
menulis surat untuk Zenko dan Hana bahwa
Sunaomi tiba dengan selamat; surat kepada
Sugita Hiroshi, memintanya datang ke Hagi
secepat mungkin; surat kepada Terada
Fumifusa, mengabarkan tentang kepulangan
Takeo dan keberadaan putranya, Fumio, dan
terakhir surat kepada Sonoda Mitsuru di
Inuyama, memberitahukan bahwa belum ada
Keputusan mengenai nasib kedua sandera;
masalah ini akan dibicarakan pada per-
temuan mendatang.
Kaede memberitahukan pada Takeo dan
Minoru tentang semua masalah terbaru yang
berkaitan dengan kota Hagi dan penduduk-
nya. Minoru mencatat dengan hati-hati ten-
tang Keputusan yang akan diambil. Di
pengujung hari yang panjang, panas serta
melelahkan, Takeo pergi mandi, dan me-
ngirim perintah agar putri kembarnya datang
menghadapnya ke sana.
Mereka menyelinap masuk ke air beruap
dengan tubuh telanjang: badan mereka tak
lagi seperti badan anak-anak, rambut mereka
panjang dan tebal. Sikap mereka lebih tenang
dari biasanya, jelas masih belum yakin apa-
kah Takeo sudah memaafkan tingkah mereka
pada hari sebelumnya.
"Kalian kelihatan lelah," kata Takeo.
"Ayah berharap kalian bekerja keras hari ini."
"Shizuka galak sekali hari ini," Miki meng-
hela napas. "Dia bilang kami perlu lebih
disiplin."
"Dan Shigeko memaksa kami menulis
begitu banyak," keluh Maya. "Jika aku tidak
punya jari seperti Ayah, apakah Lord Minoru
akan menulis untukku?"
"Ayah dulu belajar menulis, maka kalian
pun begitu," sahutnya. "Dan menulis jauh
lebih sulit bagi Ayah karena usia Ayah sudah
lebih tua. Makin muda, makin mudah
belajar. Bersyukurlah kalian memiliki guru
yang sangat baik!" Nada suaranya terdengar
tegas.
Miki memegang-megang bekas luka
ayahnya yang melintang dari leher samping
ke dada.
Takeo bicara dengan suara lebih lembut.
"Banyak hal dituntut dari kalian. Kalian
harus belajar cara ksatria, begitu pula dengan
semua rahasia Tribe. Ayah tahu itu tidak
mudah. Kalian memiliki banyak bakat:
kalian harus hati-hati menggunakannya."
Miki berkata, "Karena kejadian pada
kucing itu?"
"Coba ceritakan," sahut Takeo.
Si kembar saling bertukar pandang tanpa
bicara.
Takeo berkata, "Kalian adalah darah
daging Ayah. Kalian ditandai, seperti juga
Ayah, sebagai Kikuta. Tidak ada yang tidak
bisa kalian ceritakan pada Ayah. Maya, apa
yang terjadi pada kucing itu?"
"Aku tak bermaksud menyakiti," Maya
mulai bicara.
"Jangan bohong," Takeo memperingatkan.
Maya meneruskan, "Aku ingin melihat apa
yang akan terjadi." Suaranya kedengaran
serius; menatap lurus pada Takeo. Kelak
Maya ingin menantang tatapan ayahnya.
"Aku marah sekali dengan Mori Hiroki."
"Hiroki menatap kami," Miki menjelas-
kan. "Semua begitu. Seolah kami ini setan."
"Dia menyukai Shigeko dan tidak
menyukai kami," tutur Maya.
"Sama seperti semua orang," ujar Miki,
dan seolah diamnya Takeo melepaskan ses-
uatu dalam dirinya, Miki menangis. "Kami
dibenci karena kami kembar!"
Si kembar jarang menangis. Satu lagi sifat
yang membuat mereka nampak tidak wajar.
Maya juga menangis. "Ibu juga membenci
kami karena ibu menginginkan anak laki-
laki, dan bukannya dua anak perempuan!"
"Chiyo yang bilang pada kami," Miki
menelan ludah.
Takeo merasa hatinya remuk redam
karena kesedihan. Memang mudah menya-
yangi putri sulungnya, tapi ia lebih menya-
yangi si kembar karena mereka tidak mudah
disayangi, dan juga merasa iba pada mereka.
"Kalian sangat berharga bagi ayah," sahut-
nya. "Ayah merasa gembira karena kalian
kembar dan kalian anak perempuan. Ayah
lebih senang anak perempuan ketimbang
semua anak laki-laki di dunia ini."
"Saat Ayah ada di sini, kami merasa aman.
dan kami tak ingin melakukan hal-hal yang
buruk. Tapi Ayah sering pergi jauh."
"Ayah ingin mengajak kaliantapi tidak
selalu bisa. Kalian harus bersikap baik
bahkan saat Ayah tidak ada di sini."
"Orang-orang seharusnya tidak boleh
menatap kami," ujar Maya.
"Maya, mulai saat ini kau yang harus
berhati-hati saat menatap. Kau sudah tahu
ceritanyaAyah sudah sering ceritakan
padamutentang pertemuan Ayah dengan
raksasa Jin-emon?" tanya Takeo.
"Ya," sahut mereka serempak dengan
penuh semangat.
"Ayah menatap matanya dan dia tertidur.
Itulah sihir tidur Kikuta yang berguna untuk
melumpuhkan musuh. Itulah yang kau laku-
kan pada kucing itu, Maya. Tapi Jin-emon
bertubuh besar, setinggi gerbang kastil serta
lebih berat dari banteng. Kucing bertubuh
kecil, dan masih muda, dan sihir tidur itu
membunuhnya."
"Kucing itu tidak benar-benar mati," tutur
Maya, bergerak mendekati lalu bergelayut di
lengan kiri ayahnya. "Kucing itu men-
datangiku."
Takeo berusaha tak menunjukkan ke-
kagetannya, tak ingin membungkam putri-
nya.
"Kucing itu datang tinggal bersamaku,"
ujar Maya. "Kucing itu tidak keberatan.
Karena sebelumnya kucing itu tidak bisa
bicara, kini dia bisa bicara. Dan aku pun
tidak keberatan. Aku suka kucing itu. Aku
suka menjadi kucing."
'Tapi Jin-emon tidak mendatangi Ayah,
kan?" tanya Miki. Bagi mereka hal ini tidak
lebih aneh dibandingkan dengan kemampu-
an menghilang, atau sosok kedua, dan
mungkin tidak lebih berbahaya.
"Tidak, karena akhirnya Ayah menggorok
tenggorokannya dengan Jato. Dia mati
karena digorok, bukan karena sihir tidur itu."
"Apa Ayah marah dengan kejadian kucing
itu?" tanya Maya.
Takeo tahu kalau mereka percaya padanya,
dan ia tak ingin kehilangan kepercayaan itu,
juga sadar kalau mereka bersifat pemalu
layaknya hewan liar yang dapat kabur dalam
sekejap. Terkenang masa-masa penuh pen-
deritaan selama bersama Kikuta. kekejaman
dalam pelatihannya.
"Tidak. Ayah tidak marah," sahut Takeo
dengan tenang.
"Shizuka marah sekali," gumam Miki.
"Tapi Ayah harus tahu semuanya agar bisa
melindungi kalian, dan menghentikan kalian
agar tak menyakiti orang lain. Ayah adalah
orangtua dan juga senior kalian dalam
keluarga Kikuta. Kalian berhutang kepatuhan
pada Ayah dalam kedua hal itu."
"Kejadiannya begini," tutur Maya. "Aku
marah pada Mori Hiroki. Kulihat betapa
sayangnya dia pada kucing itu. Aku ingin dia
membayar perbuatannya karena tidak mau
menatap kami. Dan kucing itu manis sekali.
Aku ingin bermain dengannya. Maka kutatap
matanya, dan aku tidak bisa berhenti
menatapnya. Kucing itu lucu, dan aku ingin
menyakiti Hiroki, dan aku tak bisa meng-
hentikannya." Maya berhenti, menatap tak
berdaya ke arah Takeo.
"Teruskan," ujarnya.
"Aku menariknya masuk. Dari tatapan
matanya, melalui tatapan mataku. Kucing
melompat masuk ke dalam diriku. Kucing
itu melolong dan mengeong. Tapi aku tidak
bisa berhenti menatapnya. Kemudian kucing
itu mati. Tapi dia masih hidup."
"Lalu?"
"Lalu Mori Hiroki sedih, dan itu mem-
buatku senang." Maya menghela napas
panjang, seolah habis susah mengingat
pelajaran yang telah dihapalkannya. "Hanya
itu. Ayah, sungguh."
Takeo menyentuh pipi Maya. "Kau telah
berkata jujur. Tapi kau tahu betapa mem-
bingungkan perasaanmu. Pikiranmu tidak
jernih, yang justru harus sebaliknya saat
menggunakan kemampuan Tribe itu. Saat
menatap mata orang lain, kalian akan
melihat kelemahan mereka. Itulah yang
membuat mereka rapuh pada tatapan
kalian."
"Apa yang akan terjadi padaku?" tanya
Maya.
"Ayah tidak tahu. Kita harus mengamati-
mu untuk mencari tahu. Tindakanmu salah;
kau membuat kesalahan. Kau akan harus
menanggung akibatnya. Tapi kau harus ber-
janji pada Ayah untuk tidak menggunakan
sihir tidur Kikuta pada orang lain sampai
Ayah ijinkan."
"Mestinya Kenji tahu," ujar Miki, dan
mulai menangis lagi. "Dia menceritakan
tentang roh-roh hewan dan cara Tribe
memanfaatkannya."
"Kuharap dia belum mati," kata Maya di
sela-sela isak tangisnya yang baru meledak
lagi.
Dan Takeo merasakan matanya pun
menghangat, menangisi kepergian gurunya,
dan kedua putri kembarnya yang belum bisa
dilindunginya dari kerasukan yang akibatnya
pun belum bisa diperkirakannya.
Kedua putrinya berada di dekatnya, tubuh
mereka begitu mirip dengan tekstur dan
warna kulit dirinya.
"Kami tidak harus menikah dengan
Sunaomi, kan?" tanya Maya, kini lebih
tenang.
"Mengapa? Siapa yang mengatakan kalian
harus menikah dengannya?"
"Sunaomi mengatakan pada kami kalau
dia ditunangkan dengan salah satu dari
kami!"
"Hanya kalau dia benar-benar nakal,"
sahut Takeo. "Sebagai hukuman!"
"Aku tak ingin ditunangkan dengan siapa
pun," ujar Miki.
"Kelak kau pasti berubah pikiran," Takeo
menggoda.
"Aku ingin menikah dengan Miki," kata
Maya, sambil tertawa cekikikan.
"Kita berdua menikah saja," sahut Miki
sepakat.
"Lalu kalian takkan punya anak. Kalian
membutuhkan laki-laki untuk bisa punya
anak."
"Aku tak ingin punya anak," sahut Miki.
"Aku benci anak-anak," sahut Maya
setuju. "Terutama Sunaomi! Ayah tidak akan
mengangkat Sunaomi sebagai anak, kan?"
"Ayah tak membutuhkan anak laki-laki,"
sahut Takeo.
***
Pemakaman Kenji dilaksanakan keesokan
harinya, dan batu nisan didirikan untuknya
di kuil Hachiman di sebelah Tokoji, yang tak
lama kemudian menjadi tempat ziarah bagi
keluarga Muto dan anggota Tribe yang lain.
Kenji telah berpulang ke alam baka, seperti
juga Shigeru, juga Jo-An. Kini mereka
bertiga menginspirasi dan melindungi orang
yang masih hidup di dunia fana ini.*
Musim hujan plum sudah selesai dan hawa
panas musim panas dimulai. Shigeko bangun
sebelum matahari terbit dan pergi ke kuil di
tepi sungai untuk menghabiskan waktu ber-
sama si kuda hitam jantan saat udara masih
dingin. Dua kuda betina tua menggigit dan
menendang, mengajarinya sopan santun;
sedangkan kuda jantan mulai bisa menerima
kehadiran Shigeko, meringkik saat melihat-
nya dan menunjukkan tanda sayang.
"Dia tidak pernah melakukannya pada
siapa pun," komentar Mori Hiroki, memer-
hatikan kuda jantan itu menggesek-gesekkan
kepalanya di bahu Shigeko.
"Aku ingin berikan untuk ayahku," sahut
Shigeko. "Ayah tak memiliki kuda yang
disukai sejak Shun mati."
"Kuda ini sudah siap dijinakkan." ujar
Hiroki. "Tapi Anda jangan mencobanya
dulu, yang pasti jangan seorang diri. Aku
sudah terlalu tua dan lamban, sedangkan
ayah Anda terlalu sibuk."
"Tapi harus aku lakukan," bantah
Shigeko. "Kuda ini mulai menyayangiku."
Lalu pikiran itu terbersit di benaknya,
Hiroshi akan datang ke Hagi Kami bisa
menjinakkan kuda ini bersama-sama. Dan
Ayah bisa menungganginya saat kami me-
lakukan perjalanan ke Miyako.
Dinamainya kuda itu Tenba karena ada
sesuatu bersifat surgawi pada kuda itu, dan
sewaktu berderap mengelilingi padang
rumput, kuda itu tampak seolah terbang.
Hari-hari yang panas berlalu. Anak-anak
berenang di laut dan melanjutkan pelajaran
dan pelatihan dengan gembira karena sang
ayah sudah pulang. Meskipun urusan
pemerintahan membuatnya sibuk, Takeo
selalu menyempatkan waktu bersama
mereka, pada malam-malam yang hangat
ketika langit hitam kelam dan bintang-
bintang terlihat membesar, serta hembusan
lembut angin dari laut membuat kediaman
terasa dingin.
Bagi Shigeko, peristiwa besar selanjutnya
di musim panas adalah kedatangan Sugita
Hiroshi dari Maruyama. Hiroshi tinggal
bersama keluarga Otori sampai usia dua
puluh tahun lalu pindah ke Maruyama,
tempat dia menjalankan pemerintahan
wilayah milik ibu Shigeko dan suatu kelak
akan menjadi miliknya. Kedatangannya
terasa seperti kembalinya kakak laki-laki bagi
ketiga gadis itu. Setiap kali menerima surat,
Shigeko berharap membaca kalau Hiroshi
sudah menikah, karena usianya sudah dua
puluh enam tahun dan belum beristri. Hal
ini tak bisa dijelaskan, tapi dia hanya
setengah mengakui kalau dia lega saat
Hiroshi berkuda ke Hagi seorang diri, dan
tidak menyebut istri atau tunangan yang
ditinggalkan di Maruyama. Menunggu
hingga bisa bicara berdua pada Shizuka,
Shigeko membuka topik pembicaraan
dengan santai. "Shizuka, berapa usia kedua
putramu saat mereka menikah?"
"Zenko delapan belas tahun, dan Taku
tujuh belas tahun," jawab Shizuka. "Tidak
terlalu muda."
"Dan usia Taku dan Sugita sebaya, kan?"
"Ya, dan mereka lahir di tahun yang
samabibimu Hana juga lahir di tahun itu."
Shizuka tertawa. "Kukira ketiganya berharap
bisa menikahi Hana. Terutama Hiroshi yang
selalu mendambakan menjadi suami Hana:
dia amat mengagumi ibumu dan meng-
anggap Hana mirip dengannya. Taku ber-
hasil mengatasi patah hatinya, tapi sudah
menjadi rahasia umum kalau Hiroshi tak
dapat menghapus kekecewaannya, dan itulah
alasannya dia tidak menikah."
"Sungguh aneh," ujar Shigeko, setengah
ingin meneruskan pembicaraan, dan setengah
tercengang dengan rasa sakit di hatinya.
Hiroshi jatuh cinta pada Hana sehingga tak
mau menikah lagi?
"Bila ada unsur persekutuan pada diri
mereka, sudah pasti ayahmu akan menikah-
kan mereka," tutur Shizuka. "Tapi posisi
Hiroshi itu unik. Kedudukannya kurang
tinggi. Kedekatannya pada keluargamu
hampir seperti anak laki-laki di keluarga ini,
namun dia tak punya tanah warisannya
sendiri. Dia akan menyerahkan Maruyama
padamu tahun ini."
"Kuharap dia akan terus mengabdi padaku
di sana," kata Shigeko. "Tapi aku terpaksa
harus mencarikan istri untuknya! Apakah dia
memiliki perempuan simpanan?"
"Kurasa ada," sahut Shizuka. "Kebanyakan
laki-laki memiliki perempuan simpanan!"
"Ayahku tidak," sahut Shigeko.
"Memang tidak, begitu pula Lord
Shigeru." Tatapan mata Shizuka menerawang
jauh.
"Ingin tahu mengapa mereka sangat ber-
beda dengan laki-laki lain."
"Mungkin perempuan lain tidak menarik
perhatian mereka. Dan kurasa mereka tak
ingin membuat orang yang mereka sayangi
tersiksa rasa cemburu."
"Cemburu adalah perasaan yang menakut-
kan."
'Tapi untungnya kau masih terlalu muda
untuk mempunyai perasaan semacam itu,"
sahut Shizuka. "Dan ayahmu akan memilih
jodohmu dengan bijaksana. Bahkan ayahmu
memilih dengan sangat teliti, aku ingin tahu
apakah dia bisa menemukan orang yang
cukup baik."
"Tak menikah pun aku sudah bahagia,"
seru Shigeko, tapi ia tahu kalau ini tidak
sepenuhnya benar. Sejak mulai beranjak
dewasa ditemukan ia gelisah dengan
keinginan disentuh laki-laki.
"Sayang sekali para gadis tidak dibolehkan
memiliki kekasih layaknya anak laki-laki,"
katanya.
"Mereka harus sedikit lebih bijaksana,"
sahut Shizuka, tertawa. "Apakah ada orang
yang kau sukai, Shigeko? Kau sudah lebih
dewasa dari yang kukira?"
"Tentu saja tidak. Aku hanya ingin tahu
seperti apa: hal-hal yang dilakukan laki-laki
dan perempuan bersama, pernikahan, cinta."
Shigeko mengamati Hiroshi malam itu
saat makan malam. Dia tidak mirip orang
yang dimabuk cinta. Tubuhnya tidak terlalu
tinggi, kira-kira setinggi ayahnya tapi lebih
tegap dan dengan wajah lebih gemuk.
Bentuk matanya panjang dan ekspresinya
hidup, rambutnya tebal dan hitam pekat.
Tampak suasana hatinya sangat baik, penuh
optimisme tentang panen yang akan datang
dan dengan bersemangat menceritakan hasil
teknik inovasi dalam melatih kuda dan
manusia; menggoda si kembar dan memuji
Kaede, berkelakar dengan Takeo dan meng-
ingatkannya tentang mundurnya pasukan
saat badai topan dan pertempuran merebut
Hagi. Satu atau dua kali Shigeko merasa
kalau laki-laki itu menatapnya, tapi saat ia
melihat ke arahnya, Hiroshi selalu me-
mandang ke arah lain, dan hanya bicara
langsung pada Shigeko satu atau dua kali, itu
pun dengan sikap formal. Saat itu wajah
Hiroshi tak bersemangat, ekspresinya tenang,
malah hampir tak bersahabat. Mengingatkan
Shigeko pada wajah guru-gurunya di biara
saat bermeditasi; dan ingat kalau, seperti
dirinya, Hiroshi dilatih dengan Ajaran
Houou. Hal itu agak menenangkannya:
mereka selalu menjadi teman seperjuangan,
meskipun hubungan mereka tak bisa lebih
dari itu; Hiroshi selalu memahami dan
mendukungnya.
Tepat sebelum beristirahat, Hiroshi ber-
tanya padanya tentang kuda muda itu karena
Shigeko pernah menyuratinya tentang
masalah itu.
"Datanglah ke kuil besok pagi dan kau
bisa lihat sendiri," sahut Shigeko.
Sesaat Hiroshi ragu-ragu, kemudian ber-
kata, "Dengan senang hati. Ijinkan aku
mengawalmu." Nada suaranya terdengar
dingin, dan kata-katanya resmi.
Mereka berjalan berdampingan menyebe-
rangi jembatan batu, seperti yang sering
mereka lakukan ketika Shigeko masih kecil.
Udara terasa tenang, cahaya cerah dan
keemasan, saat matahari terbit di atas
pegunungan dan mengubah permukaan
tenang sungai menjadi cermin yang
berkilauan memantulkan dunia yang tampak
lebih nyata ketimbang dunia yang mereka
lalui.
Biasanya dua penjaga kastil mendampingi
Shigeko, tapi hari ini Hiroshi menyuruh
mereka pergi. Dia berpakaian untuk
menunggang kuda, mengenakan celana
panjang dan pembalut kaki, dan pedang di
sabuknya. Shigeko mengenakan pakaian yang
hampir serupa, rambutnya diikat ke belakang
dengan tali, dan hanya bersenjatakan tongkat
pendek yang disembunyikan. Shigeko men-
ceritakan tentang kuda itu, dan sikap kaku
Hiroshi perlahan luruh, dan berani berdebat
dengan Shigeko seperti yang sering dilaku-
kannya lima tahun silam. Sebaliknya, per-
debatan ini bagi Shigeko sama mengecewa-
kannya dengan sikap resmi laki-laki itu.
Dia hanya menganggapku sebagai adik,
sama seperti pada si kembar.
Matahari pagi menyinari kuil tua: Hiroki
sudah siap dan Hiroshi menyambutnya
dengan gembira karena dia menghabiskan
masa kecilnya dengan orang tua itu, belajar
ketrampilan menjinakkan dan mengembang-
biakkan kuda.
Tenba mendengar suara Shigeko dan
meringkik. Ketika mereka menghampirinya,
kuda itu berderap ke arah Shigeko, tapi
telinganya berdiri tegak dan memutar bola
matanya saat melihat Hiroki.
"Kuda ini menakutkan sekaligus tampan,"
seru Hiroshi. "Jika bisa dijinakkan, dia bisa
menjadi kuda perang yang luar biasa."
"Aku ingin menghadiahkannya kepada
Ayah," ujar Shigeko. "Tapi aku tak ingin
ayah membawanya ke kancah pertempuran!
Sekarang kita dalam kedamaian, kan?"
"Ada awan badai di kaki langit," ujar
Hiroshi. "Itu sebabnya aku dipanggil."
Tadinya aku berharap kau datang untuk
melihat kuda milikku!" kata Shigeko,
memberanikan diri menggoda.
"Bukan hanya melihat kudamu," sahutnya
pelan. Shigeko terkejut sewaktu melihat
sekilas ke arah Hiroshi, wajah laki-laki itu
agak memerah hingga ke lehernya.
Setelah beberapa saat, Shigeko bicara
dengan sikap canggung, "Kuharap kau ada
waktu untuk membantuku menjinakkannya.
Aku tak ingin orang lain yang melakukan-
nyakuda ini percaya padaku, dan
kepercayaan itu tak boleh dihancurkan, jadi
aku harus ada di sini terus."
"Nantinya kuda ini juga akan percaya
padaku," sahut Hiroshi. "Aku akan ke sini
kapan saja ayahmu tak membutuhkan diriku.
Kita akan menjinakkannya bersama-sama,
dengan cara yang pernah diajarkan pada
kita."
Ajaran Houou merupakan ajaran tentang
unsur-unsur laki-laki dan perempuan:
kekuatan yang lembut, welas asih yang kuat,
kegelapan dan cahaya, bayangan dan
matahari, yang tersembunyi serta yang
terungkap. Kelembutan saja tak bisa
menjinakkan kuda seperti ini. Dibutuhkan
juga kekuatan serta ketegasan seorang laki-
laki.
Mereka memulainya pagi itu, sebelum
hawa panas semakin kuat, membiasakan si
kuda dengan sentuhan Hiroshi, di kepala,
sekitar telinga, pinggul bagian samping dan
di bagian bawah perutnya. Kemudian mereka
menempatkan pita halus di sepanjang
punggung hingga ke leher, terakhir mengikat
dengan longgar satu pita lagi di hidung dan
kepalanyatali kekang pertamanya. Tenba
berkeringat dan kulitnya menggigil, namun
patuh pada cara mereka menanganinya.
Mori Hiroki mengamati mereka dengan
sikap setuju, dan setelah itu, ketika kuda
jantan itu dihadiahi wortel dan Shigeko serta
Hiroshi disajikan teh dingin, dia berkata,
"Wilayah lain di Tiga Negara dan di luarnya,
kuda-kuda dijinakkan dengan paksaan,
seringkah dengan kekerasan. Hewan-hewan
dipukul agar patuh. Namun ayahku selalu
percaya pada pendekatan yang lembut."
"Itu sebabnya mengapa kuda-kuda Otori
termashur," tutur Hiroshi. "Mereka jauh
lebih patuh dibandingkan kuda-kuda lain,
lebih bisa diandalkan dalam pertempuran,
dan dengan stamina yang lebih kuat, karena
mereka tidak membuang tenaga melawan si
penunggangnya dan berusaha berlari dengan
cepat! Aku selalu menggunakan metode yang
kupelajari darimu."
Wajah Shigeko bersinar. "Kita akan ber-
hasil menjinakkannya, kan?"
"Aku tak meragukan hal itu," sahut
Hiroshi, membalas senyuman Shigeko
dengan sikap hangat.*
Takeo mengetahui kerjasama putrinya
dengan Sugita Hiroshi dalam menjinakkan si
kuda jantan hitammeskipun tidak
mengetahui kalau kuda itu akan dihadiahkan
padanyakarena dia mengetahui hampir
segalanya, tidak hanya di Hagi tapi di seluruh
Tiga Negara. Kurir pergi atau berkuda
menyampaikan pesan antarkota, dan burung-
burung dara digunakan untuk mengirim
kabar darurat dari kapal di laut. Takeo
mengira Hiroshi sudah seperti kakak bagi
putrinya; terkadang mengkhawatirkan masa
depan dan statusnya yang masih melajang,
dan memikirkan pasangan yang cocok dan
berguna bagi pemuda yang telah mengabdi
dengan setia padanya sejak masih kecil.
Pemah terdengar olehnya desas-desus kalau
Hiroshi tergila-gila pada Hana; ia tidak
percaya begitu saja, mengenal karakter
Hiroshi yang kuat dan kecerdasannya
namun Hiroshi menghindari semua calon
yang diajukan. Akhirnya ia memutuskan
untuk memperbarui usahanya mencarikan
istri bagi Hiroshi dari keluarga ksatria di
Hagi.
Di satu senja yang panas pada bulan
ketujuh, tak lama setelah Festival Tanabata,
Takeo, Kaede, Shigeko dan Hiroshi pergi
melintasi teluk menuju kediaman Terada
Fumifusa. Ayah dari sahabatnya, Fumio,
mantan kepala perompak yang kini
memelihara dan mengawasi armada kapal
perang maupun kapal dagang sehingga Tiga
Negara termashur dalam perdagangan dan
keamanan dari serangan lewat laut. Kini
Terada berusia kira-kira lima puluh tahun,
namun hanya menunjukkan sedikit ke-
lemahan karena usia. Takeo sangat meng-
hargai ketajaman otak, keberanian dan
pengetahuan Terada.
Terada tidak memedulikan harta benda
indah yang diperolehnya saat menjadi
perompakdendamnya pada pemimpin
Klan Otori menjadi penggerak kekuatannya,
dan kejatuhan para paman Shigeru adalah
keinginan terbesarnya. Setelah pertempuran
merebut Hagi dan gempa bumi, dia mem-
bangun kembali rumah lamanya yang
dirancang oleh putra dan menantunya,
Eriko, sepupu keluarga Endo. Eriko
menyukai lukisan, taman dan benda-benda
yang indah: dia menulis puisi dengan goresan
kuas yang indah, dan membuat kediaman itu
tampak mewah dan memesona dilihat dari
kastil.
Bangunan itu berada di dekat kawah
gunung berapi, tempat cuaca yang tidak biasa
membuatnya dapat menanam tanaman
eksotis yang dibawa Fumio, dan tanaman
obat yang dibawa Tabib Ishida. Sifatnya yang
artistik membuatnya menjadi teman yang
disenangi Takeo dan Kaede. Putri sulung
Terada akrab dengan Shigeko karena mereka
seumur.
Paviliun kecil dibangun di atas sungai kecil
di taman, dan bunyi tenang air yang
mengalir memenuhi udara.
Kolam dipenuhi warna ungu muda dan
bunga teratai putih kekuningan, dinaungi
pepohonan aneh dari Kepulauan Selatan
yang mirip kipas. Udara terasa harum oleh
aroma adas manis dan jahe. Semua tamu
mengenakan jubah musim panas berwarna
cerah, menyaingi warna-warni kupu-kupu
yang beterbangan di antara bunga. Burung
tekukur menyerukan nyanyiannya yang
memecah kesunyian, dan jangkrik berderik
tiada henti.
Eriko memperkenalkan permainan lama di
mana para tamu harus menggubah puisi, lalu
mengapungkannya di atas nampan kayu kecil
untuk dibaca pengunjung di paviliun
sebelahnya. Kaede mahir dalam membuat
puisi semacam ini, dengan pengetahuan
luasnya tentang kiasan klasik dan kemam-
puan berpikir cepat, namun Eriko hampir
menandinginya. Mereka bersaing penuh
persahabatan.
Cangkir-cangkir sake juga diapungkan di
permukaan air yang mengalir pelan, dan
sesekali satu atau dua tamu mengambilnya
lalu diberikan kepada temannya. Irama kata-
kata dan tawa berbaur dengan suara air,
serangga serta burung membuat diri Takeo
merasakan kebahagiaan murni yang jarang
dirasakannya, menghilangkan kecemasannya
serta meringankan kesedihannya.
Takeo tengah mengamati Hiroshi yang
duduk bersama Shigeko dan putri Eriko,
Kaori, di paviliun sebelah. Usia Kaori cukup
dewasa untuk dinikahkan: mungkin dia bisa
menjadi pasangan yang cocok bagi Hiroshi;
nanti akan dibicarakannya dengan Kaede.
Kaori mirip ayahnya: tubuh berisi serta sehat.
Kaori dan Shigeko tengah tertawa melihat
usaha Hiroshi.
Namun di sela-sela tawa dan semua suara
lain di senja yang damai ini, ada suara lain,
mungkin kepakan sayap burung. Ia men-
dongak menatap langit dan melihat
sekawanan kecil bintik jauh di arah tenggara.
Sewaktu kawanan itu mendekat, semakin
jelas terlihat kalau itu adalah kawanan
burung dara yang kembali ke kediaman
Terada, tempat mereka menetas.
Burung-burung selalu kembali kemana
pun semua kapal Terada yang membawanya,
tapi arah datangnya kawanan ini membuat ia
gelisah karena di tenggara terbentang kota
bebas Akashi....
Burung-burung dara melayang di atas
kepala menuju kandang. Semua orang
mendongak ke atas mengamati. Kemudian
pesta itu ditutup dengan perasaan gembira,
tapi Takeo kini sadar akan panasnya cuaca
sore ini, dari peluh di ketiaknya, derik kasar
suara jangkrik.
Seorang pelayan keluar dari rumah, ber-
lutut di belakang Lord Terada lalu berbisik
padanya. Terada melihat ke arah Takeo dan
membuat isyarat dengan kepala. Mereka
berdua berdiri bersamaan, meminta maaf
pada para tamu, lalu pergi bersama si pelayan
itu ke dalam rumah. Begitu sampai di
beranda, Terada berkata, "Pesan dari putra-
ku." Diambilnya lembaran kertas yang
dilipat, terbuat dari sutra, lebih ringan dari
bulu.
"Gagal. Senjata sudah di tangan Saga.
Segera kembali."
Takeo melihat dari bayangan beranda ke
arah pemandangan yang indah di taman.
Didengarnya suara Kaede saat membaca,
mendengar suara yang menyambut keang-
gunan dan kepandaiannya.
"Kita harus persiapkan dewan p-
eperangan," ujarnya.
"Kita akan bertemu besok dan me-
mutuskan apa yang dilakukan."
Dewan terdiri dari Terada, ayah dan anak,
Miyoshi Kahei, Sugita Hiroshi, Muto
Shizuka, Takeo, Kaede dan Shigeko. Takeo
menceritakan tentang pertemuannya dengan
Kono, tuntutan Kaisar, jenderal baru dan
senjata yang diselundupkan. Miyoshi Kahei
ingin bertindak cepat: membangun kekuatan
militer selama musim panas, kematian Arai
Zenko dan Lord Kono lalu diikuti dengan
pemusatan pasukan di perbatasan wilayah
Timur yang bisa tiba lebih dulu di ibukota
saat musim semi, mengalahkan si Pemburu
Anjing dan membujuk Kaisar untuk mem-
pertimbangkan lagi tentang ancaman serta
penghinaan atas Otori.
"Kapalmu juga bisa memblokade Akashi,"
tuturnya pada Terada. "Pelabuhan itu harus
dalam kendali kita untuk mencegah ancaman
Arai."
Kemudian teringat kalau Zenko adalah
putra Shizuka, dan dia pun meminta maaf.
"Tapi aku tak menarik kembali saranku,"
ujarnya pada Takeo. "Sementara Zenko me-
rongrong di Barat, kau tak mungkin meng-
hadapi ancaman dari wilayah Timur."
"Putra Zenko ada di tangan kita," tutur
Kaede. "Kami rasa ini dapat membuatnya
patuh."
"Dia tak bisa dianggap sebagai sandera,"
sahut Kahei. "Inti dari adanya sandera yaitu
siap mencabut nyawa mereka. Aku tak ber-
maksud menghinamu, Takeo, tapi aku tak
percaya kau tega memerintahkan untuk
membunuh anak-anak. Orangtuanya tahu
kalau putranya aman bersamamu layaknya
berada di tangan ibunya sendiri!"
"Zenko sudah bersumpah sekali lagi
bahwa dia akan tetap setia padaku." tutur
Takeo. "Aku tak bisa menyerangnya sebelum
dia menyerang. Aku lebih memilih untuk
memercayainya, dengan harapan dia layak
mendapatkannya. Dan kita harus berusaha
untuk mempertahankan kedamaian melalui
perundingan. Aku tak akan membawa perang
saudara di Tiga Negara."
Kahei menggelengkan kepala, wajahnya
suram.
"Kakakmu, Gemba, dan yang lainnya di
Terayama menganjurkan untuk menenang-
kan Kaisar dengan berkunjung ke Miyako
tahun depan."
"Saat itulah Saga Hideki akan memper-
senjatai pasukannya dengan senjata api.
Setidaknya biarkan kami mendekati Akashi
dan mencegahnya memperdagangkan bubuk
mesiu. Karena kalau tidak, kau akan lang-
sung menuju ke kematian!"
"Aku mendukung tindakan yang tegas,"
ujar Terada. "Aku setuju dengan Miyoshi.
Semua pedagang di Akashi sudah lupa
daratan. Mereka telah menghina. Kita akan
beri mereka pelajaran." Terada tampak
merindukan masa ketika kapal-kapal milik-
nya mengendalikan semua perdagangan di
sepanjang garis pantai utara dan barat.
"Tindakan semacam itu akan membuat
geram pedagang kita sendiri," tutur Shizuka.
"Dan kita mengandalkan mereka untuk
mendapat persediaan, bubuk mesiu dan bijih
besi. Bakal sulit bertempur tanpa dukungan
itu."
"Klas pedagang mulai semakin kuat hingga
menjadi berbahaya," gerutu Terada. Takeo
tahu kalau itu sudah lama dikeluhkan
Terada, Miyoshi, Kahei dan banyak ksatria
lainnya, yang membenci para pedagang yang
semakin kaya raya dan makmur.
"Bila tidak menyerang sekarang, kelak
akan terlambat," ujar Kahei. "Itu saranku."
"Bagaimana denganmu?" Takeo bertanya
pada Hiroshi yang hingga saat ini belum
bicara.
"Aku memahami pandangan Lord
Miyoshi," kata Hiroshi. "Beliau punya
alasan. Menurut seni perang memang itu
yang terbaik. Tapi aku harus tunduk pada
kearifan para Guru Ajaran Houou. Kirimkan
pesan pada Kaisar bahwa Anda akan datang
berkunjung. Ini akan meredam rencana
serangan apa pun di pihaknya. Aku
menganjurkan, seperti Kahei, memperkuat
pasukan di wilayah Timur, menyiapkan
serangan tapi tidak menyolok. Kita harus
membangun kekuatan prajurit pejalan kaki
yang membawa senjata api, dan melatih
mereka untuk menghadapi prajurit yang
hampir sama kekuatannya karena sudah pasti
tahun depan Saga telah memiliki senjata
dalam jumlah besar. Hal itu tak bisa kita
cegah. Sementara untuk adik ipar Anda,
kurasa ikatan keluarga akan menjadi lebih
kuat ketimbang dendam apa pun yang
dipendamnya pada diri Anda, atau ambisi
apa pun untuk menyingkirkan Anda. Sekali
lagi aku menganjurkan agar jangan tergesa-
gesa, dan jangan bertindak terburu-buru."
Hiroshi memang ahli strategi yang handal,
pikir Takeo. Bahkan sejak dia masih kecil!
Takeo berpaling ke arah putrinya,
"Shigeko?"
"Aku sependapat dengan Lord Hiroshi,"
sahut Shigeko. "Jika aku ikut dengan Ayah
ke Miyako, kurasa Ajaran Houou akan
menang, bahkan untuk menghadapi
Kaisar."*
Selama di Hagi, Takeo sering bertemu
Shizuka yang tinggal di kastil untuk
menemani Kaede atau putri-putri-nya. Tidak
ada pertemuan resmi, maupun pengumuman
atas penunjukkan Shizuka sebagai ketua
Tribe.
Beberapa hari setelah pertemuan dewan
perang, di pagi hari Festival Tanabata, seolah
kebetulan, mereka berjumpa saat Takeo
hendak ke kastil. Minoru yang selalu meng-
ikuti dengan membawa peralatan menulis,
menyingkir agar mereka bisa bicara berdua
saja.
"Aku dapat pesan dari Taku," ujar Shizuka
pelan. "Tadi malam. Ishida dan Chikara
meninggalkan Hofu saat bulan purnama
terakhir. Cuaca sedang cerah: mestinya
mereka datang tidak lama lagi."
"Itu kabar baik," sahutnya. "Kau pasti
menantikan kepulangan suamimu." Lalu
Takeo berkata, karena tak ada alasan
mengapa kabar ini harus dirahasiakan, "Apa
lagi?"
"Ternyata Zenko memberi ijin orang asing
ikut bersama mereka. Dua dari mereka
berada di kapal, bersama penerjemah
merekaperempuan itu."
Takeo mengernyitkan dahi. "Apa tujuan
mereka?"
"Taku tidak mengatakannya. Tapi me-
nurutnya kau harus diberitahu."
"Menyebalkan," sahut Takeo. "Kita ter-
paksa menerima mereka dengan segala
macam upacara dan kemegahan, serta ber-
pura-pura terkesan atas hadiah tidak berharga
mereka. "Aku tidak ingin mereka merasa
bebas pergi ke mana saja sesuka hati. Aku
lebih suka mengurung mereka di satu
tempat: Hofu tempat yang sangat bagus
untuk itu. Carikan tempat yang tidak
nyaman untuk mereka tinggal, dan awasi
terus mereka. Adakah orang lain yang bisa
bicara bahasa mereka?"
Shizuka menggelengkan kepala.
"Baiklah, seseorang harus mempelajari
secepatnya. Penerjemah mereka harus meng-
ajari kita saat dia di sini." Takeo berpikir
cepat. Ia tak ingin bertemu Madaren; ia
merasa tidak nyaman atas kemunculan
adiknya. Takut pada kesulitan yang pasti
muncul dengan kehadiran adiknya itu, tapi
bila ia harus menggunakan jasa penerjemah,
maka sebaiknya memang adiknyaorang
yang memiliki hubungan dengannya.
Takeo memikirkan Kaede yang mampu
belajar dengan cepat, yang menguasai bahasa
Shin dan Tenjiku agar bisa membaca karya
klasik, sastra dan kitab suci. Ia akan minta
Kaede mempelajari bahasa orang asing dari
Madaren, dan akan menceritakan bahwa si
penerjemah itu adalah adiknya... pikiran
kalau ia akan mengurangi satu rahasia lagi
dari istrinya, anehnya justru membuatnya
bahagia.
"Cari gadis pandai yang bisa menjadi
pelayan mereka," pintanya pada Shizuka.
"Biarkan gadis itu berusaha sekuat tenaga
memahami apa yang mereka katakan. Dan
kita akan mengatur agar pelajaran diadakan
di sini."
"Kau bermaksud untuk belajar, sepupu?"
"Aku meragukan kemampuanku," sahut
Takeo. "Tapi aku yakin Kaede pasti mampu.
Kau juga."
"Aku sudah terlalu tua," sahut Shizuka
seraya tertawa. "'Tapi, Ishida cukup ber-
minat, dan sudah menyusun daftar istilah
ilmiah dan medis."
"Bagus. Biarkan dia melanjutkan pekerja-
an ini bersama mereka. Semakin banyak yang
bisa kita pelajari, semakin baik. Dan lihat apa
kau bisa cari tahu lebih banyak lagi dari
suamimu tentang tujuan mereka yang
sebenarnya, dan kedekatan mereka dengan
Zenko."
"Taku baik-baik saja?" Takeo menyuara-
kan pikiran yang muncul kemudian.
"Sepertinya begitu. Menurutku, hanya
sedikit frustrasi terjebak di wilayah Barat. Dia
baru akan berangkat bersama Lord Kono
untuk menginspeksi harta kekayaan, dan ber-
maksud melanjutkan dari sana ke
Maruyama."
"Begitu? Maka Hiroshi sebaiknya ada di
sana untuk bertemu mereka," ujar Takeo.
"Dia bisa menumpang kapal yang sama, dan
mengabari keputusan kita pada Taku."
***
Kapalnya terlihat di laut dua hari kemudian.
Shigeko mendengar lonceng dari bukit di
atas kastil berdentang sewaktu dia dan
Hiroshi menjinakkan si kuda jantan. Tenba
menerima sedikit dan membiarkan Shigeko
menuntunnya dengan tali kekang halus, tapi
mereka belum mencoba menaruh pelana,
atau beban apa pun di punggungnya selain
kain berlapis yang masih membuatnya ber-
gerak mundur dan menendang.
"Ada kapal datang," kata Shigeko, ber-
usaha melihat tapi sia-sia menentang silaunya
matahari pagi. "Kuharap itu kapal tabib
Ishida."
"Kalau benar itu kapalnya, berarti aku
harus segera kembali ke Maruyama," ujar
Hiroshi.
"Secepat itu!" Shigeko tidak bisa menahan
seruannya, kemudian merasa malu, "Ayah
bilang tabib Ishida membawa hadiah
istimewa untukku tanpa mengatakan apa
hadiahnya." Aku kedengaran seperti anak
kecil, pikirnya, kesal pada dirinya sendiri.
"Aku dengar dia membicarakan itu," sahut
Hiroshi, dia memperlakukan aku seperti anak
kecil, pikir Shigeko.
"Kau tahu apa hadiahnya?"
"Itu rahasia!" sahut Hiroshi menggoda.
"Aku tak boleh membocorkan rahasia Lord
Otori."
"Mengapa ayah hanya mengatakannya
padamu, tidak kepadaku?"
"Ayahmu tidak mengatakannya," sahut
Hiroshi dengan suara lebih lembut. "Hanya
saja dia mengharapkan cuaca cerah dan per-
jalanan yang tenang untuk hadiah itu."
"Pasti hewan," seru Shigeko dengan
gembira. "Kuda! Atau mungkin anak singa!
Beberapa hari ini cuaca cerah. Aku gembira
bila cuaca cerah saat Festival Tanabata."
Shigeko ingat keindahan malam tanpa
bulan yang tenang, percikan sinar bintang,
satu malam selama tahun ketika seorang
Puteri dan kekasihnya bisa bertemu
menyeberangi jembatan ajaib yang dibangun
burung magpies.
"Saat masih kecil aku suka sekali Festival
Tanabata." tutur Hiroshi. "Tapi kini hal itu
membuatku sedih. Karena tak ada yang
namanya pasangan pengantin impian, tidak
dalam kehidupan nyata."
Dia membicarakan tentang dirinya sendiri
dan Hana, pikir Shigeko. Dia sudah
menderita begitu lama. Dia harus menikah.
Dia akan melupakan Hana jika dia memiliki
istri dan anak. Namun Shigeko tak bisa
memaksa dirinya untuk menyarankan agar
Hiroshi menikah.
"Dulu aku suka membayangkan Putri
Bintang dengan wajah ibumu," tuturnya.
Tapi mungkin putri itu mirip denganmu,
menjinakkan kuda-kuda di surga."
Tenba, yang berjalan di antara mereka
berdua, mendadak ketakutan dan melompat
mundur saat seekor burung merpati terbang
dari atap kuil sehingga menarik pita yang
dipegang Shigeko. Secepatnya Shigeko me-
nenangkannya, tapi Tenba masih bertingkah
tidak karuan, dan melompat lalu terjatuh,
menerjang tubuh Shigeko dengan bahu.
Shigeko hampir terjatuh, tapi entah
bagaimana Hiroshi berhasil menjatuhkan
tubuhnya di antara Shigeko dan kuda itu,
dan sesaat Shigeko menyadari kekuatan
pemuda itu, dan hasratnya begitu kuat
hingga mengejutkan dirinya sendiriuntuk
dipeluk pemuda itu. Kuda itu berlari dengan
langkah panjang, tali kekangnya berayun-
ayun. Hiroshi bertanya, "Kau tidak apa-apa?
Kuda itu tidak menginjakmu, kan?"
Shigeko menggelengkan kepala, tiba-tiba
perasaannya bergejolak. Mereka berdiri
berdekatan, tidak bersentuhan. Shigeko
menemukan lagi suaranya.
"Kukira sudah cukup untuk hari ini. Kita
buat Tenba berjalan pelan lagi. Lalu aku
harus pulang untuk bersiap menerima
hadiah. Ayah pasti ingin mengadakan
upacara untuk itu."
"Tentu, Lady Shigeko," sahut Hiroshi,
sekali lagi bersikap dingin dan formal. Kuda
jantan itu membiarkannya mendekat, dan
Hiroshi menuntunnya mengembalikan
kepada Shigeko. Angin sepoi-sepoi ber-
hembus pelan dan merpati terbang melayang
di atas kepala, namun kuda muda itu ber-
jalan tenang di antara mereka berdua dengan
kepala tertunduk. Tak satu pun dari kedua-
nya bicara.
***
Di galangan kapal, kesibukan biasa di pagi
hari menjadi hening. Nelayan berhenti
membongkar muatan hasil tangkapan malam
hari berupa ikan sarden perak dan mackarel
sisik biru. Pedagang berhenti memuat
berkarung-karung garam, beras dan sutra ke
kapal bertiang lebar, dan orang-orang
berkumpul di jalanan berkerikil, menyambut
kapal dari Hofu dengan muatan anehnya.
Shigeko kembali ke kediaman lalu berganti
pakaian yang lebih sesuai untuk menyambut
hadiah untuknya. Untungnya jarak antara
gerbang kastil ke tangga pelabuhan dekat dan
bisa dilalui dengan berjalan kaki. Dia
berjalan sepanjang pantai, melewati rumah
kecil di bawah pohon pinus tempat Akane,
pelacur kelas tinggi yang pemah menghibur
Lord Shigeru, aroma semak wangi yang
ditanamnya masih tercium di udara. Shizuka
telah menunggu, tapi ibunya tetap tinggal di
rumah, mengatakan kalau merasa kurang
sehat. Takeo sudah pergi lebih dulu bersama
Sunaomi. Sewaktu Shizuka dan Shigeko
bergabung dengan Takeo, bisa dilihat susana
hati ayahnya sedang gembira: tak hentinya
melihat ke arah Shigeko yang ada di
sampingnya dan tersenyum. Shigeko ber-
harap reaksinya tidak mengecewakan
ayahnya, dan memutuskan untuk berpura-
pura senang menerima hadiah itu.
Namun, ketika kapal mendekati dermaga,
dan hewan aneh itu bisa terlihat jelas
lehernya yang panjangkekaguman Shigeko
sebesar dan setulus kerumunan orang yang
menonton. Ia begitu gembira ketika tabib
Ishida menuntun hewan itu dengan berhati-
hati menuruni tangga kapal dan menyerah-
kan kepadanya. Shigeko terpesona oleh
kelembutan dan pola aneh kulit hewan itu,
oleh bola mata yang gelap dan tatapannya
yang lembut, dihiasi bulu mata panjang dan
tebal, oleh gayanya yang anggun serta pem-
bawaan diri yang tenang selagi mengamati
lingkungan asing di hadapannya.
Takeo tertawa gembira karena kirin dalam
keadaan sehat dan juga karena reaksi
Shigeko. Shizuka menyambut suaminya
dengan kasih sayang yang tidak diperlihat-
kan, dan si bocah, Chikara, tercengang
dengan sambutan serta kerumunan,
mengenali wajah kakaknya dan berusaha
menahan tangis.
"Jangan berkecil hati," tabib Ishida
menegurnya. "Beri salam pada paman dan
sepupumu dengan baik. Sunaomi, bantu
adikmu."
"Lord Otori," Chikara berhasil bicara,
membungkuk dalam-dalam. "Lady..."
"Shigeko," ia menyela perkataan Chikara.
"Selamat datang di Hagi!"
Ishida berkata pada Takeo, "Kami
membawa penumpang lain, mungkin kurang
disambut baik."
"Ya, aku sudah dikabari Taku. Istrimu
akan menunjukkan tempat mereka meng-
inap. Nanti akan kuceritakan rencana kita
untuk mereka. Kuharap aku dapat mem-
bujukmu untuk menghibur mereka semen-
tara waktu."
Orang-orang asing ituada dua orang,
baru pertama kali datang ke Hagimuncul
di tangga kapal, membuat orang tak kalah
terperangahnya ketimbang melihat kirin.
Kedua orang itu mengenakan celana panjang
dan sepatu bot dari kulit; emas berkilauan di
leher dan dada mereka. Satu orang berwajah
agak hitam yang dipenuhi janggut berwarna
gelap; yang satunya lagi berkulit lebih pucat
dengan rambut dan jenggot berwarna karat
pucat. Warna mata orang ini juga pucat,
sehijau teh hijau; warna rambut dan mata
seperti ini membuat orang merinding, dan
Shigeko mendengar bisik-bisik, "Itukah
raksasa?" "Hantu." "Goblin."
Mereka diikuti seorang perempuan pendek
yang tampak memberitahukan tata cara yang
sopan. Setelah dibisiki perempuan muda itu,
kedua orang asing membungkuk dengan cara
yang kaku, cenderung berlagak, lalu bicara
dengan bahasa mereka yang kasar.
Takeo membalas dengan isyarat kecil
dengan kepala. Ia tak lagi tertawa: tampak
tegas, gagah dengan jubah resminya, berhias
bordiran burung bangau, serta tutup kepala
warna hitam pekat. Orang-orang asing itu
mungkin lebih tinggi dan lebih besar, tapi di
mata Shigeko, Ayahnya jauh lebih gagah.
Perempuan itu menyembah, dan ayahnya
dengan begitu ramah, pikir Shigeko, mem-
beri isyarat agar perempuan itu boleh berdiri
dan berbicara kepadanya.
Meskipun Shigeko memegang tali sutra
yang mengikat leher kirin, dan perhatiannya
tertuju pada makhluk mengagumkan ini, tapi
ia mendengar ayahnya bicara beberapa patah
kata pada orang asing itu. Ketika perempuan
itu menerjemahkan, lalu menyampaikan
jawaban orang asing itu, Shigeko seperti
mendengar sesuatu yang tidak biasa dalam
suaranya. Dilihatnya kalau perempuan itu
terpaku menatap wajah Takeo. Dia mengenal
Ayah, pikir Shigeko. Dia berani menatap
langsung wajah Ayah. Ada sesuatu dalam
tatapan perempuan itu, semacam ekspresi
akrab yang mendekati sikap tidak sopan,
yang membuat Shigeko gelisah dan bersikap
waspada.
***
Kerumunan yang ada di dermaga dihadapkan
pada keputusan yang sulit, apakah mengikuti
kirin yang luar biasa, yang dituntun Ishida
dan Shigeko menuju kuil, tempat hewan itu
akan diperlihatkan pada Mori Hiroki dan
dipersembahkan pada dewa sungai; atau
mengikuti orang asing yang sama luar
biasanya, yang dengan sebarisan pelayan yang
didampingi Shizuka membawa sejumlah
besar kotak dan bal menuju ke perahu kecil
yang akan membawa mereka menyeberangi
sungai ke tempat penginapan di sepanjang
bangunan biara tua Tokoji.
Beruntung Hagi berpenduduk banyak,
dan ketika kerumunan mulai terbagi untuk
setiap arak-arakan terdiri dari kerumunan
yang cukup besar. Orang-orang asing itu
merasa hal ini lebih menjengkelkan diban-
dingkan kirin yang menunjukkan ekspresi
kesal karena terus menjadi tontonan. Mereka
bahkan akan lebih kesal lagi dengan jauhnya
jarak tempat penginapan dari kastil dan
penjaga serta berbagai larangan yang
diberlakukan pada mereka demi melindungi
mereka. Kirin berjalan seperti yang sedari
tadi dilakukannya, dengan langkah lambat
dan hati-hati yang anggun.
"Aku langsung jatuh hati padanya," ujar
Shigeko pada ayahnya selagi mereka men-
dekati biara. "Bagaimana aku harus berterima
kasih kepada Ayah?"
"Kau harus berterima kasih pada tabib
Ishida," sahut Takeo. "Ini adalah hadiah
darinya untuk kita: hadiah yang berharga
karena dia sendiri juga sudah jatuh hati
padanya seperti halnya dirimu, dan sudah
mengenalnya cukup lama. Dia akan tunjuk-
kan cara merawatnya."
"Sungguh indah memiliki sesuatu seperti
itu di Hagi," seru Mori Hiroki saat melihat-
nya. "Betapa diberkatinya Tiga Negara!"
Dan Shigeko juga berpikir begitu. Bahkan
Tenba tampak terpikat oleh kirin, berlari ke
pagar bambu untuk memeriksa dan
menyentuhkan hidung perlahan padanya.
Satu-satunya hal yang Shigeko sedihkan yaitu
Hiroshi akan segera pergi. Tapi saat teringat
kejadian tadi pagi, berpikir mungkin
memang sebaiknya laki-laki itu pulang.*
Sewaktu kembali ke kediaman setelah
menyambut kirin, Takeo langsung bergegas
menemui Kaede. Istrinya tampak duduk di
beranda di sisi utara kediaman, sedang bicara
dengan Taro, putra sulung si tukang kayu,
Shiro. Dia dan ayahnya kembali ke Hagi
untuk membangun kembali kota itu setelah
gempa.
Takeo memberi salam dengan ceria, dan
Taro menjawab tanpa sungkan karena masa
lalu mengikat hubungan mereka dalam
jalinan persahabatan.
"Sudah lama aku hendak menciptakan
figur Dewi Welas Asih," tutur Taro, seraya
menatap kedua tangannya seolah berharap
tangan itu bisa memberi jawaban. "Lady
Otori punya usulan."
"Kau tahu rumah di dekat tepi pantai,"
kata Kaede. "Rumah itu sudah kosong
selama bertahun-tahun, sejak Akane mening-
gal. Orang bilang kalau rumah itu berhantu,
dan Akane menggunakan mantra untuk me-
mikat Lord Shigeru tapi akhirnya dia sendiri
yang terjebak dalam ilmu hitamnya. Para
pelaut mengatakan kalau arwah Akane
menyalakan lampu di bebatuan, memberi
sinyal palsu ke kapal karena dia membenci
semua pria. Kita runtuhkan saja rumahnya
lalu menyucikan tamannya. Taro dan adik-
nya bisa membangun kuil baru untuk dewa
Kannon, dan patung yang melambangkannya
akan memberkati pesisir dan teluk."
"Chiyo menceritakan tentang kisah Akane
ketika aku masih kecil," sahut Takeo. "Tapi
Shigeru tak pernah menceritakannya, begitu
pula tentang istrinya."
"Mungkin arwah kedua wanita yang telah
berpulang itu pada akhirnya bisa beristirahat
dengan tenang," kata Taro. "Aku mem-
bayangkan bangunan kecilkita tak perlu
menebang pohon-pohon pinus tapi akan
membangun di sela-sela pepohonan itu.
Kukira dengan atap rangkap dua, dengan
lekukan tajam seperti ini, dan sambungan
siku yang saling mengunci untuk menyang-
ganya."
Diperlihatkannya pada Takeo sketsa yang
telah dibuatnya untuk bangunan itu. "Atap
yang lebih rendah menyeimbangkan atap di
atasnya, memberi kesan tampilan yang kuat
serta lembut. Kuharap bisa memberi peng-
hormatan yang sama kepada Yang Diberkati.
Kuharap tadinya bisa menunjukkan sketsa
sang Dewi, tapi figurnya tetap tersembunyi
di balik kayu hingga tanganku menemukan-
nya."
"Kau akan memahat dari satu pohon?"
tanya Takeo.
"Ya, saat ini aku sedang memilih pohon
yang tepat."
Mereka membicarakan tentang berbagai
jenis pohon, usia kayu dan semacamnya.
Kemudian Taro meninggalkan mereka ber-
dua.
"Rencana yang bagus," ujar Takeo pada
Kaede sewaktu mereka tinggal berdua. "Aku
menyukai rencana itu."
"Rasanya aku punya alasan khusus untuk
bersyukur pada sang dewi," kata Kaede
pelan. "Rasa mual tadi pagi, yang pulih
dengan cepat...."
"Istriku sayang," gumamnya, dan karena
mereka hanya berdua, Takeo memeluknya.
"Aku malu," kata Kaede, seraya tertawa
kecil. "Aku sepertinya terlalu tua untuk
hamil! Shigeko sudah menjadi wanita.
Namun aku juga bahagia. Kukira aku tak
bisa hamil lagi, mengira kesempatan kita
memiliki anak laki-laki sudah sirna."
"Aku sudah sering bilang padamu, aku
bahagia dengan ketiga putri kita," ujarnya.
"Bila nanti kita tambah satu anak perempuan
lagi, aku akan gembira."
"Aku tidak ingin mengatakannya," bisik
Kaede. "Tapi aku yakin yang satu ini laki-
laki."
Takeo mendekap istrinya, berpikir tentang
mukjizat dari makhluk baru yang tumbuh
dalam tubuh istrinya. Mereka tak bicara
selama beberapa waktu, bernapas dalam
kedekatan. Kemudian langkah kaki pelayan
di lantai papan beranda menarik mereka
kembali ke dunia nyata.
"Apakah kirin tiba dengan selamat?" tanya
Kaede, karena Takeo sudah mengungkapkan
hadiah kejutan itu pada istrinya.
"Ya, kemunculannya sangat kuharapkan.
Shigeko langsung jatuh hati padanya.
Seluruh penduduk diam dalam kekaguman."
"Bisa membuat orang Otori terkagum-
kagum adalah prestasi yang sangat baik!"
sahut Kaede. "Kuharap mereka sudah meng-
gubah nyanyian tentang hewan itu. Aku akan
pergi melihatnya sendiri nanti."
"Kau tak boleh berpanas-panasan," kata
Takeo cepat. "Kau jangan terlalu lelah. Ishida
harus menengokmu, dan kau harus melaku-
kan semua yang dimintanya."
"Ishida juga tiba dengan selamat. Aku
senang, lalu bagaimana dengan si kecil
Chikara?"
"Mabuk laut beratdia malu dengan hal
itu. Tapi gembira bertemu kakaknya." Takeo
terdiam sesaat, lalu berkata, "Kita tunda dulu
soal pengangkatan mereka sampai anak kita
lahir. Aku tak ingin melambungkan harapan
yang kelak tak bisa terpenuhi, atau men-
ciptakan kerumitan nantinya."
"yang arif," sahut Kaede setuju. "Meski
aku takut Zenko dan Hana akan kecewa."
"Hanya ditunda," Takeo menekankan.
"Kau semakin bijaksana dan berhati-hati,
suamiku!" kata Kaede sambil tertawa.
"Sudah semestinya," sahutnya. "Kuharap
kini aku dapat mengendalikan sikap tergesa-
gesa dan ceroboh." Takeo menimbang-
nimbang apa yang mesti dikatakan selanjut-
nya, dan tiba pada satu keputusan, berkata,
"Ada penumpang lain dari Hofu. Dua orang
asing, dan seorang wanita yang menerjemah-
kan mereka."
"Untuk tujuan apa mereka datang?"
"Membuka peluang untuk berdagang,
kurasa; melihat lebih banyak lagi bagian
negeri ini yang masih menjadi misteri besar
bagi mereka. Aku belum sempat bicara
dengan Ishida. Mungkin dia tahu lebih
banyak. Kita harus bisa memahami mereka.
Aku ingin mau mempelajari bahasa mereka,
dibantu perempuan yang datang bersama
mereka, tapi aku tak ingin membebanimu."
"Belajar, mempelajari bahasa adalah salah
satu yang paling kugemari," sahut Kaede.
"Kelihatannya itu tugas yang cocok di saat
kegiatan lain harus dibatasi. Tentu saja aku
mau. Siapa perempuan yang datang bersama
mereka? Aku tertarik karena dia telah
menguasai bahasa asing."
Takeo berkata dengan suara pelan, "Aku
tak ingin mengejutkan dirimu, tapi aku harus
mengatakannya. Perempuan itu berasal dari
wilayah Timur, dan sempat tinggal di
Inuyama. Dia lahir di desa yang sama
denganku, dari ibu yang sama. Dia adik
perempuanku."
"Adik yang kau kira sudah tiada?" tanya
Kaede tercengang.
"Benar, adikku, Madaren."
Kaede mengernyitkan dahi. "Nama yang
aneh."
"Nama itu cukup umum digunakan di
kalangan kaum Hidden. Dia berganti nama,
kurasa, setelah peristiwa pembantaian itu.
Dia dijual ke rumah bordil oleh prajurit yang
membunuh ibunyaibukudan kakak
perempuanku. Dia melarikan diri ke Hofu,
dan bekerja di rumah bordil lainnya, tempat
di mana dia bertemu orang asing yang
bernama Don Joao: dia fasih berbicara dalam
bahasa mereka."
"Bagaimana kau tahu semua ini?"
"Kami kebetulan bertemu di penginapan
di Hofu. Saat itu aku menyamar untuk
bertemu Terada Fumio untuk memintanya
menghentikan penyelundupan senjata. Kami
saling mengenali."
"Setelah sekian tahun...?" Kaede menatap
Takeo, setengah bersimpati, setengah tak
percaya.
"Aku yakin itu dia. Kami bertemu satu
kali lagi, hanya sebentar, dan aku semakin
yakin. Aku menyelidiki tentang dirinya dan
tahu sedikit riwayat hidupnya. Kukatakan
padanya kalau aku akan menjamin hidupnya
tapi tidak ingin bertemu dengannya lagi.
Jarak di antara kami sudah begitu lebar. Tapi
kini dia datang ke sini.... Wajar kalau dia
tertarik dalam pergaulan orang asing, karena
inti ajaran mereka serupa dengan kaum
Hidden. Aku takkan mengakuinya sebagai
saudaraku, tapi desas-desus mungkin akan
tersebar, dan aku ingin kau mengetahui
kebenarannya dariku."
"Kurasa dia bermanfaat bagi kita sebagai
jurubahasa maupun guru. "Bisakah kau
bujuk dia untuk menjadi mata-mata?"
Sepertinya Kaede berusaha menyembunyikan
kekagetannya dan bicara secara masuk akal.
"Aku yakin dia bisa menjadi sumber
informasi, dengan disengaja atau tidak. Tapi
informasi mengalir dari dua arah. Dia bisa
berguna untuk menanamkan pemikiran kita
pada kedua orang asing itu. Aku memintamu
untuk memperlakukannya dengan baik, bah-
kan dengan hormat, tapi jangan pernah
membicarakan tentang diriku padanya."
"Apakah dia mirip denganmu? Aku ingin
sekali bertemu dengannya."
Takeo menggeleng. "Dia mirip ibunya."
Kaede berkata, "Kau kedengaran sangat
dingin. Tidakkah kau gembira menemukan-
nya masih hidup? Kau tidak ingin mem-
bawanya masuk ke dalam keluargamu?"
"Kukira dia sudah mati. Aku menangisi
kematiannya serta kematian yang lainnya.
Kini aku tidak tahu harus bersikap bagai-
mana: aku sudah berubah menjadi orang
yang berbeda dari bocah yang pernah
menjadi kakaknya. Kesenjangan derajat dan
status kami sudah menganga lebar. Terlebih
lagi, dia penganut kepercayaan yang saleh:
sedangkan aku tak memercayai kepercayaan
mana pun, dan tidak lagi mengikuti
kepercayaan masa kecilku. Aku curiga kalau
orang-orang asing itu ingin menyebarkan
kepercayaan mereka. Siapa yang tahu
alasannya? Aku tak bisa membiarkan siapa
pun mengira bisa memengaruhi diriku,
karena aku harus melindungi mereka semua
dari kedua belah pihak, mungkin alasan
orang-orang itu untuk memecah belah rakyat
kita."
"Tak seorang pun yang menyaksikan
dirimu melakukan upacara di biara atau kuil
merasa yakin akan ketidakpercayaanmu,"
ujar Kaede. "Dan bagaimana dengan kuil dan
patung baruku?"
"Kau tahu kemampuanku sebagai pemain
sandiwara," sahut Takco dengan nada getir,
"Aku sungguh bahagia berpura-pura punya
kepercayaan demi kepentingan stabilitas
negara. Tapi bila kau salah satu orang
Hidden, mutlak tidak boleh berpura-pura
bila sudah menyangkut masalah kepercayaan.
Dirimu terpampang jelas oleh Yang Maha
Melihat, tatapan tanpa belas kasihan Tuhan."
Andai ayahku tidak memihak kaum Hidden,
mungkin dia masih hidup, pikirnya. Dan aku
akan menjadi orang lain.
"Tentu tuhan kaum Hidden itu Maha
Pengampun, kan?" seru Kaede.
"Bagi penganutnya, mungkin. Sedangkan
yang lainnya dikutuk ke neraka untuk
selamanya."
"Aku tidak percaya itu!" sahut Kaede,
setelah sesaat tenggelam dalam pikirannya.
"Begitu pula aku. Tapi itulah yang di-
percayai kaum Hidden, begitu juga orang-
orang asing itu. Kita harus sangat berhati-
hati dengan merekabila mereka telah
berpikir kita dikutuk, mereka mungkin
merasa benar untuk memperlakukan kita
dengan cara menghina atau keji."
Dilihatnya Kaede agak gemetar, dan takut
kalau istrinya merasakan suatu firasat.*
Pada bulan kedelapan tibalah Festival Obon.
Tepi pantai dan sungai dipenuhi orang,
bentuk tarian mereka tampak jelas diterangi
kembang api yang bersinar terang. Lampion
yang tak terhitung jumlahnya mengapung di
gelapnya permukaan air. Arwah orang yang
mati disambut kembali, dirayakan dengan
jamuan, lalu diucapkan selamat jalan dengan
gabungan antara perasaan sedih sekaligus
gembira, ketakutan dan kegembiraan. Maya
dan Miki menyalakan lilin bagi Kenji yang
amat mereka rindukan, tapi kesedihan
mereka yang tulus tak menghalangi mereka
dari kegiatan senggang baru, menyiksa
Sunaomi dan Chikara. Mereka menguping
pembicaraan dan tahu ada usulan untuk
mengangkat salah satu atau kedua anak itu.
Melihat kasih sayang Kaede pada kedua
bocah itu, mereka menduga itu karena kedua
anak itu laki-laki.
Mereka tak diberitahu tentang kehamilan
Kaede, tapi sifat mereka yang selalu memer-
hatikan, akhirnya mereka tahu. Kenyataan
bahwa hal itu tidak dibicarakan secara
terang-terangan membuat mereka gelisah.
Hari-hari di musim panas terasa panjang dan
panas: semua orang mudah marah. Shigeko
tampak semakin cepat memasuki masa
kedewasaan dan menjadi makin menjauh.
Dia lebih banyak menghabiskan waktu
dengan ayah, membicarakan tentang kun-
jungan ke ibukota tahun depan, serta hal-hal
lain yang menyangkut urusan kenegaraan.
Shizuka sibuk dengan administrasi Tribe.
Si kembar tak diijinkan keluar berdua saja,
tapi mereka sudah terampil dengan pelatihan
Tribe. Meskipun tak diijinkan mengguna-
kannya, namun rasa jenuh dan diabaikan
membuat mereka mencoba hasil pelatihan
mereka.
"Apa gunanya semua pelatihan itu bila
tidak digunakan?" gerutu Maya pelan, dan
Miki setuju dengannya.
Miki dapat menggunakan sosok kedua
cukup lama untuk memberi kesan kalau
Maya ada di ruangan sementara Maya
menghilang agar bisa menakuti Sunaomi dan
Chikara dengan hembusan napas seperti
desah napas hantu di tengkuk, atau sentuhan
di rambut. Mereka mematuhi peraturan
untuk tidak keluyuran di luar, namun aturan
itu menjengkelkan mereka: keduanya ingin
menjelajahi kota yang sibuk, hutan di
seberang sungai, area di sekitar gunung
berapi, dan hutan berbukit di atas kastil.
"Di sana ada goblin," kata Maya kepada
Sunaomi, "dengan hidung panjang dan mata
yang selalu mengintai!"
Maya menunjuk ke arah bukit, tempat
pepohonan yang begitu lebat hingga
kelihatan tak bisa ditembus. Dua layang-
layang bergulung-gulung di atas mereka. Sore
pada hari ketiga Festival Obon, keempat anak
itu berada di taman. Hari terasa menyesak-
kan; bahkan di taman, di bawah pepohonan,
tetap saja terasa panas tak terkira.
"Aku tidak takut pada tengu," sahut
Sunaomi. "Aku tidak takut pada apa pun!"
"Tengu yang ini suka makan anak laki-
laki," bisik Miki. "Mereka memakannya
mentah-mentahi"
"Seperti macan?" sahut Sunaomi seraya
mengejek, sehingga membuat Maya makin
kesal. Ia belum melupakan kata-kata
Sunaomi pada ayahnya, anggapan yang
terucap tanpa disadarinya, tentang keung-
gulan anak lelaki: Lagipula, mereka hanyalah
anak perempuan. Maya ingin membalas
perkataan itu. Dirasakan si kucing berputar-
putar di dalam dirinya, dan melemaskan jari-
jarinya.
"Mereka tak bisa mengerjai kita di sini,"
kata Chikara gugup. "Terlalu banyak
penjaga."
"Memang mudah bersikap berani saat
dikelilingi penjaga," kata Maya pada
Sunaomi. "Jika kau memang pemberani, kau
pasti berani keluar sendirian!"
"Aku tidak diijinkan," sahutnya.
"Kau takut!"
"Tidak!"
"Ya sudah, pergilah keluar. Aku tidak
takut. Aku sudah pernah pergi ke rumah
Akane, walaupun arwahnya gentayangan di
rumah itu. Aku pernah melihatnya."
"Akane membenci anak laki-laki," bisik
Miki. "Dia mengubur anak laki-laki hidup-
hidup di tamannya supaya semak-semak
tumbuh subur dan wangi."
"Sunaomi takkan berani ke sana," kata
Maya dengan setengah tersenyum.
"Di Kumamoto aku dikirim ke
pemakaman saat malam hari untuk mem-
bawa pulang sebuah lentera," tutur Sunaomi.
"Aku tak melihat satu pun hantu!"
"Kalau begitu, pergilah ke rumah Akane
dan bawa pulang beberapa tangkai bunga."
"Itu mudah," hardik Sunaomi. "Hanya
saja aku tidak diperbolehkanayahmu yang
bilang begitu."
"Kau takut," kata Maya.
'Tidak mudah keluar tanpa terlihat."
"Mudah jika kau tidak takut. Itu cuma
alasanmu saja." Maya berdiri dan berjalan ke
pinggiran dinding laut. "Kau turun lewat
dinding ini saat laut surut dan berjalan di
atas bebatuan menuju pantai." Sunaomi
mengikutinya, dan Maya menunjuk rumah
Akane yang kosong dan kelihatan muram.
Rumah itu sudah setengah dibongkar karena
akan dibangun kuil. Bangunan itu tak lagi
berbentuk rumah, tapi belum menjadi kuil,
mengesankan persimpangan antara dunia
nyata dan alam baka. Gelombang sudah
hampir naik, sebagian menampakkan
bebatuan yang menonjol dan licin. "Kau bisa
pergi malam ini." Maya berpaling ke arah
Sunaomi, menahan tatapan bocah itu selama
beberapa saat.
"Maya!" seru Miki memperingatkan.
"Oh, maaf, sepupu! Aku lupa. Aku tak
boleh menatap orang lain. Aku sudah
berjanji pada Ayah." Cepat-cepai Maya
menampar pipi Sunaomi untuk menyadar-
kannya, lalu kembali pada Chikara.
"Kau tahu, bila kau menatap mataku maka
kau akan tertidur dan tidak akan terbangun
lagi!"
Sunaomi menghampiri untuk membela
adiknya. 'Tahukah kalian kalau kalian akan
dibunuh jika tinggal di Kumamoto? Di sana
kami membunuh orang kembar!"
"Aku tidak percaya sedikit pun apa yang
kau katakan," sahut Maya. "Semua orang
lahu kalau Arai adalah pengkhianat dan
pengecut."
Sunaomi menegakkan badan dengan
bangga. "Jika kau anak laki-laki, aku akan
membunuhmu. Tapi karena kau hanya anak
perempuan, aku akan ke rumah itu dan
membawa pulang apa pun yang kau minta."
Saat matahari mulai terbenam, langit
tampak cerah tanpa angin, namun saat bulan
mulai naik, gumpalan awan aneh berwarna
kelabu berarak dari timur, melenyapkan
bintang dan akhirnya menelan bulan. Laut
dan daratan berbaur menjadi satu. Api
terakhir masih mengepulkan asap di pantai;
selain itu tak ada api lain lagi.
Sunaomi adalah putra sulung dalam
keluarga ksatria. Sejak kecil dia dilatih
dengan disiplin dan diajari untuk mengatasi
rasa takut. Tak sulit baginya, meskipun baru
delapan tahun, untuk tetap terjaga sampai
tengah malam. Sunaomi, meski dengan
keberanian yang mantap, dia tetap gelisah
dan lebih takut karena tak mematuhi paman-
nya ketimbang bahaya terluka atau pun
hantu. Para pengawal yang mendampinginya
sejak dari Hofu tinggal di aula di kota atas
perintah Lord Otori: penjaga kastil sebagian
besar berada di gerbang dan di sekitar
dinding depan. Pasukan patroli berjalan
melintasi taman dalam jarak waktu yang
teratur. Sunaomi mendengar suara mereka
melewati pintu yang terbuka dari ruangan
tempat dia dan Chikara tidur, bersama dua
pelayan yang merawat mereka. Kedua gadis
pelayan itu tidur cepat, salah satunya
mendengkur. Sunaomi cepat-cepat berdiri,
siap mengatakan kalau ia ingin ke kamar
mandi bila mereka terbangun, namun tak
satu pun dari keduanya bergerak.
Di luar, malam terasa tenang. Kastil
maupun kota sudah terlelap. Di bawah
dinding, laut bergumam lembut. Hampir
tidak bisa melihat apa-apa, Sunaomi
menghela napas panjang dan mulai meraba-
raba jalan yang dilaluinya menuruni landaian
besar di dinding batu besar yang dirapatkan.
Beberapa kali mengira kalau dirinya terjepit,
tak bisa naik atau turun; memikirkan tentang
monster yang muncul dari laut, ikan atau
gurita raksasa yang bisa menelannya ke dalam
kegelapan. Laut terdengar meraung, kini
lebih keras lagi. Bisa terdengar olehnya
pusaran air di bebatuan.
Ketika kakinya yang bersandal jerami
menyentuh permukaan bebatuan, dia ter-
peleset dan hampir jatuh ke dalam air.
Menggaruk berusaha mencengkeram sesuatu
untuk pegangan, dirasakannya kulit kerang
setajam pisau di telapak kaki dan lututnya.
Ombak merayap di bawah tubuhnya,
menyebabkan luka tadi terasa perih. Seraya
menggertakkan gigi, dia bergeser sedikit demi
sedikit bak kepiting ke arah api terakhir yang
masih mengepulkan asap, menuju ke pantai.
Pantai tampak kelabu pucat; ombak
berdesis berbuih putih. Ketika sampai di atas
pasir, dia lega merasakan kelembutan di
telapak kakinya. Lalu berganti rumput kaku;
Sunaomi tersandung dan terus berjalan
dengan merangkak ke hutan kecil tempat
pepohonan pinus bermunculan di sekeliling-
nya. Suara burung hantu terdengar di atas
kepala membuatnya melonjak terkejut, dan
bentuk burung yang seperti hantu itu sesaat
mengapung di hadapannya dengan kepakan
sayap.
Cahaya api berada tepat di belakangnya.
Sunaomi berhenti sebentar, meringkuk di
balik pepohonan. Tercium olehnya bau
damar yang terbawa asap api unggun tadi
dan aroma kuat lainnya yang terasa manis
dan memikat.
Wangi tanaman di taman Akane diperkuat
dengan darah dan tulang anak laki-laki.
Anak laki-laki sering disuruh pergi ke
makam atau tempat eksekusi di malam hari
untuk uji nyali. Sunaomi sudah menyom-
bongkan diri pada Maya kalau dia tak pernah
melihat hantu. Tapi itu bukan berarti dia tak
percaya akan keberadaannya: perempuan
berleher panjang bak ular dan gigi setajam
kucing, makhluk bermata satu serta tanpa
tangan dan kaki, bandit tanpa kepala yang
marah karena dihukum mati, orang yang
mati penasaran, akan balas dendam dengan
memangsa darah manusia.
Sunaomi menelan ludah dengan susah
payah, lalu berusaha menahan gemetar yang
semakin melemaskan tubuhnya. Aku adalah
Arai Sunaomi, katanya dalam hati, putra
Zenko, cucu Daiichi. Aku tak takut pada apa
pun.
Dipaksa dirinya untuk berdiri, lalu ber-
jalan ke depan, walau kakinya terasa berat,
dan tak tahan ingin buang air kecil. Ia men-
capai dinding taman, lekukan atap di
belakangnya. Gerbang terbuka lebar; dinding
mulai runtuh.
Ketika melangkah masuk ke gerbang,
tubuhnya terhalang sarang laba-laba, jaring-
nya lengket di wajah dan rambutnya.
Napasnya makin memburu, tapi dia berkata
pada dirinya sendiri, Jangan menangis, aku
tidak boleh menangis, meskipun bisa dirasa-
kannya air mata mulai mengambang di
pelupuk mata.
Rumah itu gelap gulita. Sesuatu berlari
cepat menyeberangi beranda, mungkin
kucing, atau tikus besar. Ia menggapaikan
tangannya seakan mengikuti bau wangi itu
sampai ke belakang rumah lalu sampai ke
taman. Kucing itupasti kucingtiba-tiba
melolong dari balik bayang-bayang.
Sunaomi bisa melihat bunganya: satu-
satunya benda yang terlihat dalam kegelapan.
Dia bergegas ke arah bunga itu, dan dengan
sembarangan mencabut beberapa tangkai.
Dia lalu lari, tapi tersandung sebongkah batu
dan jatuh terjerembab. Bau tanah dan rasa-
nya mengingatkannya pada pemakaman dan
mayat, dan betapa tak lama lagi dia akan ter-
baring di kuburan, merasakan sensasi ter-
akhir dalam hidupnya.
Lalu dia memaksakan diri berjalan me-
rangkak sekuat tenaga dan meludahkan tanah
di mulutnya. Sunaomi berdiri, menggapai
dan mematahkan sebatang ranting. Semak
itu segera mengeluarkan getah berbau tajam,
dan Sunaomi mendengar langkah kaki di di
belakangnya.
Saat berbalik, matanya langsung silau
terkena cahaya. Yang terlihat hanyalah satu
sosok setengah badan seorang perempuan,
tapi hanya sebagian badan, yang pasti baru
keluar dari liang lahat. Bayangan bergerak-
gerak di atasnya; tangan itu terulur ke arah
Sunaomi. Lenteranya agak sedikit naik;
cahaya jatuh tepat di wajah perempuan itu.
Perempuan itu tidak punya mata, mulut juga
hidung.
Pertahanan dirinya bobol. Sunaomi
menjerit; air terasa mengalir di celananya.
Dibuangnya ranting yang ada di tangannya.
"Maafkan aku, Lady Akane. Maaf. Ku-
mohon jangan sakiti aku. Jangan kubur aku!"
"Apa-apaan ini?" ada suara, suara manusia,
suara laki-laki. "Apa yang sedang kau laku-
kan tengah malam begini?" Tapi Sunaomi
tak mampu menjawab.
***
Taro yang menginap di rumah Akane sambil
mengerjakan patung, segera membawa bocah
itu kembali ke kastil. Sunaomi tidak terluka,
selain ketakutan setengah mati. Keesokan
paginya dia tidak mengakui, namun luka
telah tertoreh di hatinya, dan meskipun
sudah pulih, luka yang masih membekas
mengandung kebencian yang mendalam ter-
hadap Maya dan Miki. Sejak itu, Sunaomi
terus merenungkan kematian kakeknya, dan
serangan Klan Otori terhadap Arai. Pikiran
kanak-kanaknya mencari cara untuk me-
nyakiti Maya dan Miki. Dia mulai meng-
ambil hati para perempuan penghuni rumah
itu, menebar pesona dan menghibur mereka;
lagipula sebagian besar dari mereka menyukai
anak laki-laki. Sunaomi merindukan ibunya,
tapi nalurinya mengatakan bahwa ia bisa
mendapatkan tempat yang tinggi dalam kasih
sayang bibinya, Kaede, jauh lebih tinggi
ketimbang pada si kembar.
***
Takeo dan Kaede merasa gusar atas kejadian
ini. Jika Sunaomi terbunuh atau terluka
parah saat dalam perlindungan mereka, ter-
lepas dari kesedihan orang di kastil
menyayangi kedua bocah, maka strategi
untuk meredam dan membendung Zenko
akan hancur berantakan. Takeo juga
memarahi Sunaomi atas ketidakpatuhan dan
keberaniannya yang gegabah, dan menanyai-
nya penuh selidik tentang alasannya, curiga
kalau keponakannya tak akan melakukan hal
itu tanpa ada yang memancingnya. Tidak
butuh waktu lama untuk mengungkap
kebenarannya, dan kemudian giliran Maya
menghadapi kemarahan ayahnya.
Kali ini Takeo lebih gusar pada Maya,
karena putrinya tidak menunjukkan penye-
salan ataupun rasa bersalah, dan tatapan
matanya kejam dan tanpa belas kasihan, bak
seekor hewan. Dia tidak menangis, bahkan
ketika Kaede mengutarakan ketidak-
senangannya dan menamparnya beberapa
kali.
"Maya benar-benar keterlaluan," kata
Kaede, berlinang air mata karena kesal. "Dia
tidak bisa tinggal di sini. Bila dia tak bisa
dipercaya tinggal bersama anak laki-laki..."
Takeo mendengar kecemasan Kaede pada
bayi yang dikandungnya. Ia tak ingin
mengirim Maya pergi; Ia merasa putrinya
butuh pengawasannya, tapi ia terlalu sibuk
untuk terus berada di samping putrinya.
"Tak baik menginginkan putri kandung-
mu pergi jauh, dan lebih menyayangi putra
orang lain," kata Maya pelan.
Kaede menamparnya lagi. "Beraninya
benar kau bicara seperti itu padaku, ibumu
sendiri? Kau tahu apa tentang urusan negara?
Semua yang kami lakukan ada alasan politis.
Akan selalu seperti ini. Kau putri Lord Otori.
Kau tidak bisa bersikap seperti anak-anak
lain."
Shizuka berkata, "Dia menyadarinya: dia
memiliki kemampuan Tribe yang tidak boleh
dia gunakan sebagai putri seorang ksatria.
Sungguh sayang bila kemampuan seperti itu
disia-siakan."
Maya berbisik, "Kalau begitu, biarkan aku
menjadi putri seorang Tribe."
"Maya perlu pengawasan dan pelatihan.
Tapi siapa yang mengetahui hal semacam ini
dalam keluarga Muto? Bahkan kau, Shizuka,
dengan darah Kikuta, tak punya pengalaman
dengan kerasukan semacam ini."
"Kau mengajarkan banyak kemampuan
Tribe pada putraku," sahut Shizuka. "Mung-
kin Taku adalah orang yang paling tepat."
"Tapi Taku harus tetap di wilayah Barat.
Kita tak bisa memintanya kemari hanya
untuk kepentingan Maya."
"Maka kirim Maya kepadanya."
Takeo menghela napas. "Sepertinya hanya
itu jalan keluarnya. Adakah yang dapat
mengantar Maya?"
"Ada seorang gadis; dia baru datang dari
desa Muto bersama adiknya. Mereka berdua
bekerja di rumah penginapan orang asing
saat ini."
"Siapa namanya?"
"Sada: kerabat dari istri Kenji, Seiko."
Takeo mengangguk: kini ia ingat gadis itu;
bertubuh tinggi dan tegap, dan bisa beralih
rupa menjadi laki-laki, penyamaran yang
sering digunakan saat melaksanakan tugas
Tribe.
"Kau akan menemui Taku di Maruyama,"
kata Takeo pada Maya. "Kau harus
mematuhi Sada."
Sunaomi berusaha menghindar, tapi
sebelum pergi Maya memojokkan bocah itu,
seraya berbisik, "Kau gagal dalam uji nyali
itu. Sudah kubilang kalau Arai pengecut."
"Aku ke rumah itu," sahutnya. Taro ada di
sana. Dia yang memaksaku pulang."
Maya tersenyum. "Kau tidak bawa
rantingnya!"
"Tidak ada bunga di sana!"
"Tidak ada bunga! Kau memetik sebatang.
Lalu kau buang, dan mengompol di celana.
Aku melihatmu."
"Kau tidak ada di sana!"
"Ya, aku di sana."
Sunaomi berteriak memanggil pelayan,
tapi Maya sudah pergi.*
Seiring musim panas berganti musim gugur,
Takeo bersiap untuk bepergian lagi. Sudah
menjadi kebiasaan negeri ini kendalikan dari
Yamagata dari akhir bulan kesembilan hingga
puncak musim dingin, tapi ia terpaksa ber-
angkat lebih awal karena kematian Matsuda
Shingen; Miyoshi Gemba membawa kabar
ini ke Hagi dan Takeo langsung berangkat ke
Terayama bersama Gemba dan Shigeko.
Laporan kerja selama musim panasber-
bagai keputusan, perencanaan pertanian sena
keuangan, kode etik hukum, dan hasil
pengadilandibagi-bagi dalam kotak dan
keranjang pada barisan panjang kuda beban.
Tak ada yang perlu disesali atas kepergian
Matsuda. Tujuan hidupnya telah tercapai,
jiwanya merupakan kesatuan antara kemur-
nian dan kekuatan. Cita-citanya siap diterus-
kan murid-muridnya: Takeo dan Shigeko,
sena banyak yang lainnya. Namun Takeo
begitu merindukan, dan merasa kehilangan
orang bijak tersebut sebagai kerugian bagi
Tiga Negara.
Makoto kini menggantikan kedudukannya
sebagai Kepala Biara, dan berganti nama
menjadi Eikan, tapi Takeo tetap meng-
gunakan nama lamanya. Setetah upacara pe-
makaman selesai, mereka melanjutkan per-
jalanan ke Yamagata. Ia senang karena tahu
Makoto tetap akan mendukungnya; dan ia
memikirkan dengan penuh kerinduan saat ia
akan mengundurkan diri ke Terayama dan
sisa hidupnya dengan meditasi dan melukis.
Gemba menemani mereka ke Yamagata,
tempat berbagai urusan administrasi menyita
seluruh perhatian Takeo. Shigeko bangun
lebih awal setiap pagi untuk berlatih me-
nunggang kuda dan memanah bersama
Gemba untuk kemudian menghadiri se-
bagian besar rapat bersamanya.
Tepat sebelum berangkat ke Maruyama
pada minggu pertama di bulan kesepuluh,
surat datang dari Hagi. Takeo membacanya
dengan penuh semangat, dan segera mem-
beritahukan kabar tentang keluarga pada
putri sulungnya.
"Ibumu pindah bersama kedua bocah itu
ke rumah lama Lord Shigeru. Dan ibumu
mulai membelajari bahasa orang-orang asing
itu."
"Dari si juru bahasa?" Shigeko ingin
bertanya lagi pada ayahnya, tapi Minoru dan
pelayan rumah Miyoshi ada bersama mereka
seperti biasa, serta Jun dan Shin yang berada
di luar tapi tetap masih bisa mendengar.
Setelah itu, Shigeko mendapat kesempatan
saat mereka berdua berjalan di taman.
"Ayah hams menceritakan lebih banyak
lagi tentang orang-orang asing itu," katanya.
"Apakah sebaiknya mereka diijinkan ber-
dagang di Maruyama?"
"Ayah ingin mereka berada di tempat yang
bisa kita awasi," sahut Takeo. "Mereka akan
tinggal di Hagi selama musim dingin. Kita
harus belajar sebanyak mungkin tentang
bahasa, adat kebiasaan dan tujuan mereka."
"Juru bahasa itu: dia memandang ayah
dengan pandangan aneh, seakan dia
mengenal Ayah dengan baik."
Sesaat Takeo ragu. Daun berguguran di
taman yang tenang, menyelimuti tanah
dengan onggokan berwama emas. Saat itu
hari sudah senja, kabut merangkak naik dari
parit yang mengelilingi bangunan sehingga
mengaburkan garis bentuk dan detil.
"Ibumu tahu siapa dia, tapi orang lain
tidak." akhimya ia berkata. "Ayah akan
ceritakan kepadamu, tapi simpan rahasia ini
baik-baik. Namanya Madaren; itu nama yang
dipakai kaum Hidden. Mereka memiliki
kepercayaan yang sama dengan para orang
asing, dan dulu pernah dibantai oleh Klan
Tohan. Semua keluarganya dibunuh, kecuali
kakak laki-lakinya yang diselamatkan oleh
Lord Shigeru."
Bola mata Shigeko terbelalak dan urat
nadinya berdenyut cepat. Ayahnya ter-
senyum.
"Ya, anak itu adalah Ayah. Saat itu Ayah
bernama Tomasu, tapi Shigeru mengganti
nama Ayah menjadi Takeo. Madaren adalah
adik perempuanku: kami lahir dari satu ibu,
tapi lain bapakayahku, seperti kau tahu,
berasal dari Tribe. Selama ini Ayah mengira
dia sudah mati."
"Sungguh luar biasa," ujar Shigeko, lalu
dengan sifatnya yang lekas bersimpati, "Pasti
hidupnya menderita."
"Dia berhasil bertahan, belajar bahasa
asing, meraih semua kesempatan yang ada,"
sahut Takeo. "Madaren melakukannya lebih
baik dibandingkan orang lain. Kini dia dalam
perlindungan Ayah, dan diijinkan mengajar-
kan ibumu." Setelah beberapa saat, ia
menambahkan, "Dari dulu memang sudah
banyak kaum Hidden di Maruyama. Lady
Naomi melindungi mereka karena dia juga
mengikuti ajaran mereka. Kau harus ber-
kenalan dengan pemimpin mereka. Jo-An,
tentu saja, juga salah satu pengikutnya, serta
banyak mantan gelandangan masih tinggal di
pedesaan di sekitar kota."
Shigeko melihat wajah ayahnya muram.
dan tak ingin membahas lebih jauh lagi topik
pembicaraan yang mengingatkan Ayahnya
pada kenangan yang menyakitkan.
"Ayah sangsi bisa hidup bahkan separuh
dari usia Matsuda," lanjut Takeo dengan
sangat serius. "Kelak, keamanan mereka ini
ada di tanganmu. Tapi jangan memercayai
orang asing, begitu juga pada Madaren,
meskipun dia kerabatmu. Dan ingat untuk
menghormati semua kepercayaan, tapi
jangan ikuti satu pun dari semua itu, karena
itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh
seorang pemimpin sejati."
Shigeko merenungkan hal ini selama be-
berapa saat, "Bolehkah aku bertanya lagi?"
"Tentu. Kau boleh tanya apa saja dan
kapan saja. Ayah tak ingin menyembunyikan
apa pun darimu."
"Ramalan membenarkan kekuasaan Ayah
seperti yang ditakdirkan dan direstui Surga.
Burung houou bersarang lagi di Tiga Negara.
Bahkan kita memiliki kirinsalah satu tanda
adanya penguasa yang adil. Apa Ayah
memercayai semua ini?"
"Ayah tidak memercayai sepenuhnya,"
sahut Takeo. "Ayah sangat bersyukur atas
semua yang dianugerahkan Surga pada Ayah,
dan Ayah berharap tidak menyalahgunakan
kekuasaan yang telah diberikan kepada
Ayah."
"Orang tua semakin lama semakin akan
bertindak bodoh," tambahnya nngan "Bila
itu terjadi, kau harus mendorong Ayah untuk
mengundurkan diri. Meskipun, Ayah tak
berharap hidup sampai tua."
"Aku ingin Ayah tidak pernah mati," seru
Shigeko, mendadak ketakutan.
"Ayah akan mati dengan bahagia karena
tahu akan meninggalkan semuanya di tangan
yang aman," sahutnya, teraenyum. Tapi
Shigeko tahu kalau ayahnya menyembu-
nyikan banyak kekhawatiran.
***
Beberapa hari kemudian ia dan Gemba
menyeberangi jembatan di dekat Kibi, dan
Takeo mengenang masa lalu bersama
Gemba: pergi dari Terayama di tengah
guyuran hujan, bantuan Jo-An bersama
kelompok gelandangannya, dan kematian si
raksasa, Jin-Emon. Biara dewa rubah yang
ada di tepi sungai kini, secara aneh, diiden-
tikkan pada Jo-An dan sekarang dia dipuja di
sini.
"Pada saat itu Amano Tenzo memberiku
Shun," ujar Takeo. Ditepuknya leher kuda
hitam yang sedang ditungganginya. "Kuda
yang ini cukup menyenangkan, tapi Shun
membuatku tercengang pada peperangan
pertama kami. Dia lebih tahu banyak tentang
peperangan ketimbang diriku sendiri!"
"Kukira dia sudah mati sekarang?" tanya
Gemba.
"Ya, dia mati dua tahun lalu. Tidak ada
kuda seperti dia. Tahukah kau kalau Shun
ternyata adalah kuda Takeshi? Mori Hiroki
yang mengatakannya."
"Aku tidak tahu," sahut Gemba.
Tapi, Shigeko sudah tahu hal itu, dia
tumbuh dewasa bersama salah seorang yang
melegenda itu. Kuda coklat kemerahan itu
dijinakkan oleh Lord Takeshi, adik Shigeru,
yang membawanya ke Yamagata. Takeshi
dibunuh prajurit Tohan, dan kuda itu meng-
hilang sampai Amano Tenzo membeli dan
memberikannya kepada Takeo. Ia memikir-
kan dengan gembira atas hadiah rahasia yang
akan ia berikan untuk ayahnya. Ia sudah
lama berharap akan ke Maruyama karena ia
memang bermaksud menghadiahkan kuda
itu sebagai kejutan saat upacara yang akan
datang.
Memikirkan legenda dan hewan-hewan
yang mengagumkan memunculkan gagasan
di benaknya. Begitu cemerlangnya gagasan
itu hingga ia ingin langsung mengatakannya.
"Ayah, saat kita ke Miyako tahun depan,
kita hadiahkan kirin kepada Kaisar."
Gemba tertawa terbahak-bahak. "Hadiah
yang sempurna! Hadiah yang belum pernah
terlihat di ibukota!"
Takeo berpaling dari pelana dan menatap
Shigeko. "Gagasan yang menakjubkan. Tapi
Ayah telah memberikan kirin untukmu.
Ayah tak ingin memintanya kembali. Dan
apakah hewan itu dapat bertahan dalam
perjalanan sejauh itu?"
"Hewan itu berhasil menempuh per-
jalanan dengan kapal. Aku bisa menemani-
nya sampai ke Akashi. Mungkin Lord
Gemba atau Lord Hiroshi bisa ikut ber-
samaku."
"Kaisar serta orang istana akan terpesona
dengan hadiah itu," kata Gemba, pipi
tembamnya merona merah karena senang.
"Sepertinya Lord Saga akan takluk pada Lady
Shigeko."
Shigeko, menunggang kuda melalui
pedesaan di musim gugur yang damai
menuju wilayah yang akan segera menjadi
miliknya, tempat ia akan bertemu Hiroshi
lagi. merasakan kalau mereka memang
direstui Surga. dan Ajaran Houou, ajaran
kedamaian akan menang.*
Setelah kematian Muto Kenji, jasadnya
dibuang ke parit dan tertimbun tanah. Tidak
ada benda yang menandakan tempat itu, tapi
Hisao tidak sulit menemukannya karena ibu-
nya membimbing langkahnya ke sana.
Seringkali hujan turun tiba-tiba selagi ia
melewatinya, membiaskan sinar matahari
menjadi penggalan-penggalan bianglala di
awan yang membumbung tinggi. Hisao
melihatnya dan memanjatkan doa bagi arwah
kakeknya agar dapat menempuh jalan aman
menuju alam baka dan kelahiran kembali
yang lebih baik pada kehidupan kelak. Ia
kemudian melihat ke bawah, ke barisan
pegunungan yang terbentang ke timur dan
utara, untuk melihat apakah ada orang yang
datang Hisao merasa lega tapi juga menyesal
karena arwah kakeknya telah keluar. Arwah
itu menggantung di tepi kesadaran seperti
juga arwah ibunya, membuatnya sakit kepala
dengan tuntutan yang tak bisa dipahami. Ia
hanya mengenal kakeknya sebentar, namun
telah merindukannya: Kenji bunuh diri atas
kemauannya sendiri; Hisao senang arwah
kakeknya sudah pergi dengan damai, tapi
menyesali kematiannya, dan walaupun tidak
pernah membicarakan hal itu, dia membenci
Akio karena menjadi penyebabnya.
Musim panas berlalu dan tak ada yang
datang.
Penduduk desa merasa khawatir selama
musim panas, terutama Kotaro Gosaburo,
karena tak ada kabar tentang nasib anak-
anaknya yang ditahan di Inuyama. Desas-
desus dan spekulasi kian bertambah: bahwa
mereka sekarat karena disiksa, bahwa salah
satu atau keduanya sudah tewas. Gosaburo
semakin kurus, lipatan kulit keriputnya
semakin bergelayut, sinar matanya hampa.
Akio makin tak sabar pada Gosaburo; dia
menjadi cepat kesal dan sikapnya menjadi
susah ditebak. Hisao agak senang men-
dengar kabar baik tentang eksekusi para
pemuda itu karena akan memadamkan
harapan Gosaburo dan menguatkan ke-
putusannya untuk balas dendam.
Bunga lili musim gugur berwarna merah
tua pekat tumbuh di atas jasad Kenji, meski
tak ada yang menanamnya. Burung-burung
mulai bermigrasi ke utara, dan malam
dipenuhi jeritan angsa dan kepakan sayap
mereka. Rembulan di bulan kesembilan
tampak besar dan keemasan. Pohon maple
dan pohon sumac berubah warna menjadi
merah tua, pohon beech berwarna tembaga,
willow dan ginko berwarna keemasan. Hari-
hari dilalui Hisao dengan memperbaiki
pematang sebelum musim dingin, menyebar
dedaunan kering dan kotoran hewan di
sawah, mengumpulkan kayu bakar dari
hutan. Sistem pengairannya berhasil: sawah
di pegunungan menghasilkan panen kedelai,
wortel dan labu yang baik. la membuat
penggaruk tanah baru sehingga pupuk ter-
sebar lebih merata, dan bereksperimen
dengan bilah kapak, bobot, sudut serta ke-
tajamannya. Ada sebuah tempat penempaan
besi di desa itu, dan Hisao ke sana saat ada
waktu luang untuk memerhatikan dan
membantu meniup panas dengan alat peng-
embus dalam proses mengubah besi menjadi
baja.
Di awal bulan ketujuh, Imai Kazuo
dikirim ke Inuyama untuk mencari berita.
Dia kembali di pertengahan musim gugur
dengan kabar gembira namun membingung-
kan: para sandera masih hidup, masih di-
tahan di Inuyama. Dia juga membawa kabar
lain: Lady Otori sedang hamil dan Lord
Otori mengirim utusan dengan prosesi yang
mewah ke ibukota. Rombongan itu berada di
Inuyama di waktu yang bersamaan dengan
Kazuo, dan baru akan berangkat ke Miyako.
Sikap Akio kurang senang dengan
potongan berita yang pertama, iri pada berita
yang kedua, dan amat gelisah dengan berita
yang ketiga.
"Mengapa Otori melakukan pendekatan
pada Kaisar?" tanyanya pada Kazuo. "Apa
maksudnya?"
"Kaisar telah menunjuk jenderal baru,
Saga Hideki, yang selama sepuluh tahun ini
sibuk memperluas kekuasaannya di seluruh
penjuru wilayah Timur. Kini muncul seorang
ksatria yang bisa menantang Otori."
Mata Akio berkilap dengan ekspresi yang
tidak biasa. "Ada yang berubah; aku dapat
merasakannya. Otori menjadi lebih rapuh,
bereaksi pada ancaman semacam itu. Kita
harus ambil bagian dalam kejatuhannya:
dengan bersembunyi kita tidak bisa me-
nunggu sampai orang lain membawa kabar
kematiannya kepada kita."
"Memang ada tanda-tanda kelemahan,"
Kazuo sepakat. "Mengutus orang ke Kaisar,
dan anak-anak itu masih hidup... sebelumnya
ia tidak ragu membunuh keluarga Kikuta."
"Muto Kenji berhasil mengetahui ke-
beradaan kita," ujar Akio penuh per-
timbangan. Takeo pasti sudah tahu tempat
kita ini. Aku tidak percaya dia maupun Taku
akan membiarkan kematian Kenji begitu saja
tanpa membalas dendam, kecuali mereka di-
sibukkan dengan hal-hal yang lebih men-
desak."
"Ini waktunya bagimu untuk bepergian
lagi," kata Kazuo. "Ada banyak keluarga
Kikuta di Akashi. Keluarga kita yang ada di
Tiga Negara ini juga butuh tuntunan, dan
akan mengikutimu bila kau yang ke sana."
"Kalau begitu kita pergi ke Akashi lebih
dulu," sahut Akio.
***
Sebagai anak, ayah Hisao mengajarinya
ketrampilan teater keliling Kikutamemain-
kan drum, atraksi lempar bola, menyanyikan
balada kuno yang disukai penduduk desa,
tentang perang zaman dulu, pertikaian,
pengkhianatan dan tindakan balas dendam
yang selalu mereka lakukan dalam perjalanan
ke seluruh Tiga Negara. Seminggu setelah
pulangnya Kazuo, Akio mulai berlatih atraksi
lempar bola lagi; sandal jerami disiapkan
dalam jumlah banyak, asinan persimmon dan
chestnut dikumpulkan lalu dikemas, jimat-
jimat dikeluarkan dan dibersihkan, senjata-
senjata diasah.
Hisao bukanlah pemain pertunjukan yang
berbakat: terlalu pemalu dan tidak menik-
mati menjadi pusat perhatian, tapi kombinasi
antara pukulan dan makian Akio telah men-
jadikannya cukup terampil. Ia jarang mem-
buat kesalahan, ia pun hapal semua lirik
lagu-lagu, walaupun orang mengeluhkan
kalau ia seperti bergumam sehingga sulit
didengar. Gagasan untuk bepergian mem-
buat ia bersemangat sekaligus takut. Tak
sabar untuk segera berada di jalan, pergi
meninggalkan desa, melihat hal-hal baru, tapi
kurang bersemangat dengan pertunjukan dan
gelisah meninggalkan makam kakeknya.
Gosaburo gembira menerima kabar dari
Kazuo, dan menanyainya dengan penuh
selidik. Dia tidak langsung bicara pada Akio,
tapi di malam sebelum keberangkatan
mereka, ketika Hisao tengah bersiap untuk
tidur, Gosaburo menghampiri pintu kamar
dan meminta apakah bisa bicara berdua
dengan Akio.
Akio sudah setengah telanjang dan Hisao
bisa melihat ekspresi kemarahan ayahnya,
tapi memberi isyarat agar tamunya boleh
masuk dengan menggerakkan kepala.
Gosaburo melangkah ke dalam kamar,
menggeser tutup pintu lalu berlutut dengan
gugup.
"Keponakan," ujarnya, seolah menekankan
otoritas usia. "Sudah saatnya kita berunding
dengan Otori. Tiga Negara semakin kaya dan
makmur sementara kita bersembunyi di
pegunungan, nyaris kelaparan dan tidak lama
akan musim dingin. Kita juga bisa ber-
kembang: pengaruh kita bisa diperluas
melalui perdagangan. Hentikanlah semua
pertikaian ini."
Akio menjawab, "Tidak akan."
Gosaburo menghela napas panjang. "Aku
akan kembali ke Matsue. Aku akan pergi
besok pagi."
"Tidak ada yang boleh pergi meninggalkan
keluarga Kikuta," Akio memperingatkan,
suaranya datar.
"Aku mulai membusuk di sini. Kita semua
juga. Otori membiarkan anak-anakku tetap
hidup. Mari kita terima lawarannya untuk
berdamai. Aku akan setia padamu. Aku akan
bekerja untukmu di Matsue seperti yang
pernah kulakukan, menyediakan dana,
menyimpan catatan...."
"Begitu Takeodan juga Takumati,
baru kita bicara tentang perdamaian," sahut
Akio. "Sekarang enyahlah. Aku lelah, dan
kehadiranmu membuatku jijik."
Tak lama setelah Gosaburo pergi, Akio
memadamkan lampu. Hisao sudah ber-
baring: malam itu terasa hangat dan ia tidak
menarik selimut untuk menutupi tubuhnya.
Penggalan cahaya menari-nari di balik
kelopak matanya. Sesaat ia berpikir tentang
sepupu-sepupunya dan ingin tahu bagaimana
cara mereka mati di Inuyama, tapi ke-
mudian ia mendengarkan gerakan Akio:
setiap sel dalam tubuh orang itu seakan
merindukan belai kasih sayang.
Kemarahan Akio membuatnya bersikap
kasar dan gegabah. Hisao berusaha untuk
tidak bersuara karena kekerasan yang
sewaktu-waktu akan menimpa dirinya. Suara
Akio terdengar hampir lembut saat
menyuruh ia tidur, jangan bangun, dan
jangan pedulikan apa pun yang akan di-
degarnya, dan Hisao merasakan kelembutan
sesaat yang amat dirindukannya saat rambut-
nya dibelai sang ayah. Setelah Akio pergi
meninggalkan kamar, Hisao membenamkan
diri di balik selimut dan berusaha menutup
telinganya. Terdengar beberapa kali suara
pelan, seseorang tercekik dan meronta-roma:
suara berdebuk berat, diseret di atas papan,
lalu ke tanah.
Aku sudah tidur, kata Hisao berulang kali
pada dirinya sampai tiba-tiba, sebelum Akio
kembali, ia sudah tertidur nyenyak dan tanpa
mimpi bak orang mati.
Keesokan harinya tubuh Gosaburo ter-
geletak di lorong. Dia mati dibunuh dengan
garotte. Tak seorang pun berani menangisi
kematiannya.
"Tak ada yang boleh meninggalkan Kikuta
dan bebas pergi tanpa hukuman," kata Akio
pada Hisao sewaktu mereka bersiap
berangkat. "Ingat itu. Takeo dan Isamu,
ayahnya, berani meninggalkan Tribe. Isamu
sudah dieksekusi, dan Takeo akan meng-
alami hal yang sama."
***
Akashi berkembang selama bertahun-tahun
dalam konflik dan kebingungan sehingga
para saudagar mengambil keuntungan dari
kebutuhan pangan dan senjata para ksatria.
Begitu mereka kaya, mereka tidak ingin
kekayaan mereka dirampas ksatria yang sama
sehingga mereka bergabung untuk melin-
dungi barang serta usaha mereka. Kota ini
dikelilingi parit lebar yang digali untuk
melindungi diri dari musuh, dan masing-
masing parit dengan sepuluh jembatannya
dijaga prajurit dari masing-masing kesatuan.
Ada beberapa kuil besar yang melindungi
dan mendukung perdagangan, baik dalam
bidang materi maupun spiritual.
Saat para penguasa semakin berkuasa,
mereka mencari benda dan pakaian yang
indah, karya seni dan kemewahan lain dari
Shin dan daerah yang lebih jauh lagi, dan
pedagang pelabuhan bebas ini menyediakan-
nya dengan senang hati. Keluarga Tribe
pernah menjadi pedagang yang paling ber-
kuasa di kota itu, tapi meningkatnya
kesejahteraan di Tiga Negara serta per-
musuhan dengan Otori membuat banyak
yang pindah ke Hofu.
"Masa kejayaan telah berlalu," kata
Jizaemon, pemilik usaha importir sukses,
pada Akio saat menyambutnya dengan sikap
setengah hati. "Kita harus bergerak. Kita bisa
lebih berkiprah dalam banyak peristiwa
dengan menyediakan senjata dan kebutuhan
lainnya. Mari kita dukung persiapan perang,
dan dari keuntungan kita bisa menghindari
akibatnya."
Mengira ayahnya akan bertindak seperti
yang dilakukan pada Gosaburo, Hisao sedih.
Ia tak ingin Jizaemon mati sebelum mem-
perlihatkan sebagian dari nana bendanya, alat
yang bisa menghitung waktu, botol kaca dan
cabung minuman, cermin dan makanan baru
yang lezat, manis dan pedas, kayu manis dan
gula: kata-kata yang belum pernah di-
dengarnya.
Perjalanan terasa panjang dan melelahkan.
Baik Akio maupun Kazuo tidak muda lagi,
dan penampilan mereka sebagai seniman
jalanan sudah hilang gregetnya. Lagu-lagu
mereka telah ketinggalan jaman dan tak lagi
populer. Kehadiran mereka di jalanan tidak
mendapat sambutan baik, bahkan di satu
desa yang tidak ramah: tak seorang pun mau
memberi mereka tempat menginap sehingga
mereka terpaksa berjalan lagi semalaman.
Saat ini Hisao tengah mengamati ayahnya,
dia melihat kalau ayahnya sudah tua. Di desa
kelahirannya, Akio adalah Ketua Kikuta,
ditakuti dan dihormati semua orang;
sementara di sini, dengan pakaian tua yang
lusuh, ayahnya kelihatan seperti bukan siapa-
siapa. Hisao merasa iba, lalu berusaha
menyingkirkan perasaan itu, karena rasa iba,
seperti biasa, membuka dirinya pada suara-
suara arwah. Sakit kepala yang tak asing
mulai terasa lagi: separuh dunia menyelinap
ke balik kabut; perempuan itu berbisik, tapi
ia tidak mau mendengarkan.
"Baiklah, mungkin kau benar," terdengar
olehnya Akio bicara, seolah dari kejauhan.
"Tapi yang pasti peperangan tidak bisa
dihindari selamanya. Kami sudah mendengar
tentang kurir-kurir yang dikirim Otori
kepada Kaisar."
"Ya, mereka berangkat hanya selang
beberapa minggu sebelum kau datang: aku
belum pernah melihat prosesi yang begitu
mewah. Otori pasti benar-benar kaya, dan
lebih dari itu, dikaruniai dengan selera dan
tingkah laku serta tutur bahasa yang halus:
kabarnya itu karena pengaruh istrinya..."
"Dan Kaisar memiliki jenderal baru?" Akio
memotong perkataan si pedagang yang
penuh semangat.
"Benar, dan ada lagi, sepupu, tak lama lagi
jenderal itu akan memiliki senjata-senjata
baru. Kabarnya, itu sebabnya Lord Otori
mencari dukungan Kaisar."
"Apa maksudmu?"
"Selama bertahun-tahun Otori member-
lakukan embargo senjata api. Tapi baru-baru
ini embargo itu dilanggar, dan senjata api
diselundupkan keluar Hofukabamya
dengan bantuan Arai Zenko! Kau kenal
Terada Fumio?"
Akio mengangguk.
"Nah, Fumio tiba dua hari setelah
penyelundupan itu dan berusaha mendapat-
kannya kembali. Dia gusar sekali; pertama-
tama dia menawarkan sejumlah besar uang,
lalu mengancam akan kembali dengan
pasukan lalu membakar habis kota itu jika
tidak dikembalikan. Tapi sudah terlambat:
senjata itu sudah dalam perjalanan ke tempat
Saga. Dan harga jual besi dan bubuk mesiu
itu setinggi langit, sepupu, setinggi langit!"
Jizaemon menuang secangkir lagi sake dan
memaksa mereka minum bersamanya.
"Tak ada yang memedulikan ancaman
Terada," katanya tertawa kecil. "Dia tak lebih
dari perompak. Dulu dia juga penyelundup.
Dan Lord Otori takkan menyerang kota itu,
tidak selama dia membutuhkan pedagang itu
untuk memberi makan dan mempersenjatai
pasukannya."
Hisao penasaran dengan jawaban Akio
yang singkat. Ayahnya memang sudah
mabuk berat, dan mengangguk setuju pada
semua perkataan Jizaemon, meskipun dahi-
nya makin berkerut dan wajahnya makin
muram.
Hisao terbangun tengah malam men-
dengar ayahnya berbisik pada Kazuo.
Dirasakan seluruh ototnya menegang, dan
setengah berharap mendengar lagi suara
pelan pembunuhan, tapi kedua orang itu
tengah membicarakan hal lain: tentang Arai
Zenko yang membiarkan senjata api keluar
dari jaringan Otori.
Hisao tahu riwayat Zenko: putra sulung
Muto Shizuka, cucu keponakan Kenji, dan
saudara sepupu dirinya. Zenko satu-satunya
keluarga Muto yang tidak dikutuk keluarga
Kikuta: dia tak terlibat dalam kematian
Kotaro, dan kabarnya dia tak sepenuhnya
setia pada Takeo. Dicurigai kalau dia
menyalahkan Takeo atas kematian ayahnya,
dan bahkan menyimpan hasrat untuk balas
dendam.
"Zenko kuat sekaligus ambisius," bisik
Kazuo. "Jika dia berusaha mengambil hati
Lord Saga, dia pasti tengah bersiap bergerak
melawan Si Anjing."
"Waktu yang tepat untuk mendekati
Zenko," gumam Akio. "Takeo sedang men-
dapat ancaman dari Timur; jika Zenko
menyerang dari Barat maka dia akan terjebak
di antara dua wilayah tersebut."
"Kurasa Zenko akan menyambutmu,"
sahut Kazuo. "Sejak kematian Kenji, Zenko
yang seharusnya menjadi Ketua Muto.
Kapan lagi waktu yang tepat untuk pergi ke
keluarga Muto guna memperbaiki keretakan
dalam Tribe, guna menyatukan kembali
semua keluarga?"
Jizaemon, mungkin senang berhasil
menyingkirkan tamunya, menyediakan surat
ijin perjalanan dan memberi pakaian bam
serta barang dagangan lainnya. Diaturnya
agar mereka bisa bepergian dengan kapal
pedagang, dan dalam beberapa hari mereka
angkat sauh ke Kumamoto melalui Hofu,
memanfaatkan cuaca cerah dan tenang di
akhir musim gugur.*
Maya tidak bepergian sebagai putri Lord
Otori, tapi dengan menyamar cara Tribe.
Sebagai adik Sada, dan mereka pergi ke
Maruyama untuk bertemu dengan kerabat di
sana dan mencan pekerjaan setelah kematian
orangtua mereka. Maya menyukai perannya
sebagai anak yatim piatu, dan menyenangkan
baginya membayangkan kalau orangtuanya
mati karena marah, terutama pada ibunya,
dan amat terluka dengan sikap kedua orang-
tuanya karena lebih sayang pada Sunaomi.
Maya pernah melihat Sunaomi menjadi anak
cengeng karena mengira melihat hantu
yang sebenarnya adalah patung Kanon maha
Penyayang yang belum selesai dibuat. Maya
semakin membenci rasa takut Sunaomi
karena itu belum apa-apa dibandingkan apa
yang pernah dilihatnya di malam yang sama,
malam ketiga Perayaan Obon.
Waktu itu ia mengikuti Sunaomi dengan
menggunakan kemampuan Tribe, tapi saat
sampai di pantai, ada sesuatu di malam itu
yang menyentuh perasaannya, dan suara si
kucing berbicara dalam dirinya, mengatakan,
"Lihatlah apa yang bisa kulihat!"
Awalnya seperti permainan: latar yang
gelap dadak terang, bola matanya yang besar
menangkap semua gerakan yang ada, hewan-
hewan kecil berlarian ke sana kemari, getaran
dedaunan, semburan air terbawa angin. Lalu
tubuhnya melemas dan meregang seperti
tubuh kucing, dan Maya menyadari kalau
pantai dan hutan pinus penuh dengan hantu.
Ia melihat hantu-hantu itu dengan peng-
lihatan si kucing, wajah mereka abu-abu,
jubah mereka putih, tubuh pucat mereka
mengambang di permukaan tanah. Arwah
orang-orang mati itu memalingkan pan-
dangan ke arah Maya dan si kucing menang-
gapi mereka, mengenali penyesalan pahit,
dendam tak berkesudahan, hasrat yang tak
terpenuhi dalam diri mereka.
Maya menjerit kaget; si kucing melolong.
Maya berusaha kembali ke tubuh manusia-
nya; cakar si kucing menggaruk-garuk batu
kerikil di pasir pantai: melompat ke
pepohonan di sekitar rumah itu. Arwah-
arwah mengejar Maya, berdesakan di
sekelilingnya, sentuhan mereka terasa
sedingin es di kulit hewan berbulunya. Ter-
dengar olehnya suara-suara seperti gemerisik
dedaunan tertiup angin musim gugur, penuh
kesedihan dan kelaparan.
"Di mana Penguasa kami? Bawa kami
padanya. Kami sedang menunggunya."
Kata-kata mereka memenuhi dirinya bak
teror yang menakutkan, meskipun tidak me-
mahami apa maksudnya, seperti dalam
mimpi buruk ketika sepotong kalimat yang
tak jelas membuat orang yang bermimpi me
rasa ketakutan setengah mati. Terdengar
olehnya derak ranting patah, lalu melihat
seorang laki-laki keluar dari rumah yang baru
separuh hancur dengan membawa lentera.
Para arwah gentayangan tadi mundur terkena
sinar lentera, dan membuat bola mata Maya
mengecil dan akhirnya tidak bisa lagi melihat
mereka. Tapi didengarnya Sunaomi menjerit,
dan juga gemericik air ketika bocah itu
kencing di celana. Penghinaan atas ketakutan
Sunaomi membantu Maya mengatasi ke-
takutannya sendiri, cukup untuk mundur ke
semak-semak dan pulang tanpa terlihat ke
kastii. Ia tidak ingat bagaimana si kucing
meninggalkan dirinya hingga ia kembali
menjadi Maya, sama tidak jelasnya dengan
apa yang membuat tubuh kucing merasuk
dalam sendirinya. Tapi ia juga tak bisa
menyingkirkan ingatan akan pandangan
mata si kucing dan suara-suara bergema dari
arwah gentayangan. Di mana Penguasa kami?
Maya ketakutan setengah mati, tak ingin
melihat dan mendengar dengan cara seperti
itu lagi, dan berusaha melindungi dirinya
dari kerasukan arwah si kucing. Ia telah
mewarisi sifat kejam dari Kikuta seiring
dengan banyak bakat yang lain. Tapi kucing
itu mendatanginya lewat mimpi, meminta,
menakuti-nakuti dan membujuk dirinya.
***
"Kau bisa jadi mata-mata yang sangat hebat!"
seru Sada setelah malam pertama di atas
kapal.
"Aku lebih suka jadi mata-mata ketimbang
harus menikah dengan lord," sahut Maya.
"Aku ingin sepertimu, atau seperti Shizuka
dulu."
Maya menatap gelombang ke Timur,
tempat kota Hagi hampir menghilang di
kejauhan: Pulau Oshima juga terbentang
jauh di belakang mereka, hanya awan di atas
gunung berapi di pulau itu yang terlihat.
Mereka telah melewatinya semalam, dan itu
membuat Maya menyesal karena pernah
mendengar banyak cerita tentang para
perompak jaman dulu dan kunjungan ayah-
nya kepada Lord Terada. Ia ingin melihat-
nya, tapi kapal tidak boleh berangkat ter-
lambat: angin timur laut hanya terjadi
beberapa hari lagi, dan mereka mem-
butuhkannya untuk membantu kapal melaju
ke pantai Barat.
"Dulu Shizuka suka melakukan sesuka
hatinya," sambung Maya. "Tapi dia menikah
dengan tabib Ishida, dan kini dia sama saja
seperti istri-istri yang lainnya."
Sada tertawa. "Jangan meremehkan Muto
Shizuka! Dia selalu jauh lebih dari yang
kelihatannya."
"Dia juga nenek Sunaomi," gerutu Maya.
"Kau iri, Maya; itu masalahmu!"
"Sangat tidak adil," sahut gadis itu. "Andai
aku laki-laki, tak masalah kalau aku kembar.
Andai aku laki-laki, Sunaomi tidak akan
datang tinggal bersama kami, dan Ayah tak-
kan berpikir untuk mengangkatnya sebagai
anak!" Dan aku takkan berpikir untuk
menantang pengecut cilik itu pergi ke biara.
Maya menatap Sada. "Pernahkah kau ber-
harap menjadi seorang laki-laki?"
"Ya, sering, ketika aku masih kecil. Bahkan
di kalangan Tribe, di mana perempuan diberi
banyak kebebasan, anak laki-laki sepertinya
lebih dihargai. Aku selalu menentang
mereka, selalu berusaha mengalahkan
mereka. Muto Kenji sering bilang itu sebab-
nya kenapa aku tumbuh besar sama tinggi
dan kuatnya seperti laki-laki. Dia meng-
ajariku cara meniru anak laki-laki, bicara
dengan gaya bahasa mereka dan menirukan
gerakan mereka. Kini aku bisa jadi laki-laki
atau perempuan, dan itu sebabnya aku
menyukainya."
"Kenji mengajarkan kita hal yang sama!"
seru Maya, karena seperti semua anak-anak
Tribe, ia belajar bicara dengan gaya bahasa
laki-laki dan perempuan, serta gerakan, dan
bisa bertingkah seperti keduanya.
Sada mengamatinya. "Ya, kau bisa menjadi
laki-laki."
"Benar, aku tidak menyesal disuruh pergi
jauh," Maya berusaha meyakinkan. "Karena
aku suka padamudan aku sayang pada
Taku!"
"Semua orang menyayangi Taku," Sada
tertawa.
Maya tidak sempat menangkap lebih
banyak lagi bahasa pelaut yang menggoda
dan nyaris tak bisa dimengerti karena
gelombang laut mulai naik. Gerakan kapal
yang naik turun membuatnya pusing dan
tubuhnya terasa tidak enak. Sada merawatnya
tanpa mengeluh atau kata-kata bersimpati,
memegang tengkuknya sewaktu ia muntah
dan setelah itu mengelap wajahnya, mem-
bujuknya untuk minum teh untuk mem-
basahi bibirnya. Ketika sampai di tahap yang
paling buruk, Maya berbaring di pangkuan
Sada yang melingkarkan lengannya yang
panjang dan dingin di alis Maya. Sada seperti
merasa kalau di balik kulit Maya ada sifat
hewan, bak kulit bulu hewan, gelap, padat
dan berat, tapi juga lembut untuk disentuh.
Maya merasakan sentuhan itu seperti
sentuhan seorang pengasuh atau seorang ibu;
ia tersadar ketika kapal berbelok mengitari
tanjung tepat saat angin berubah arah dan
angin barat berhembus membawa mereka ke
tepi pantai, lalu menatap wajah Sada yang
tajam, dengan tulang pipi tinggi seperti anak
laki-laki, dan berpikir betapa bahagianya bisa
selamanya berbaring di dalam pelukannya,
dan merasakan sekujur tubuhnya bereaksi
dengan menggeliat. Pada saat itu hasrat
menyelimuti dirinya pada gadis yang lebih
tua itu, kombinasi antara kekaguman dan
kebutuhan: itu pertama kalinya Maya jatuh
cinta. Diregangkan tubuhnya untuk me-
meluk Sada, melingkarkan lengan di tubuh-
nya, merasakan otot kuat seperti otot laki-
laki, dan kelembutan yang tak terduga dari
buah dadanya. Diusap-usapkan hidungnya
ke leher Sada, hampir seperti anak kecil,
sekaligus seperti hewan.
"Kuanggap sikapmu ini berarti kau sudah
baikan?" tanya Sada, balas memeluknya.
"Sedikit. Tadi rasanya sakit sekali. Aku tak
ingin naik kapal lagi!" Maya berhenti
sebentar lalu melanjutkan, "Kau mencintaiku
Sada?"
"Pertanyaan apa itu?"
"Aku bermimpi kau mencintaiku. Tapi
aku tidak yakin apakah aku bermimpi,
alaukah...."
"Atau apa?"
"Atau si kucing."
"Mimpi sepeni apa yang dialami kucing
itu?" tanya Sada dengan enggan.
"Mimpi yang dialami hewan." Maya
tengah menatap ke pantai di kejauhan, bukit
ditumbuhi pinus di atasnya yang muncul
dari air laut berwarna biru tua, bebatuan
hitam yang berada di tepiannya dengan
ombak keabuan hijau dan putih. Permukaan
air di sekitar teluk lebih tenang, dan sampai
ke muara, rak kayu penopang rumput laut
dan kapal nelayan berbadan cembung tengah
ditarik ke pantai, tempat rumput laut
tumbuh. Orang-orang meringkuk di tepi
pantai, membetulkan jala dan menjaga agar
api unggun tetap menyala yang memaksa
garam keluar dari air laut.
"Aku tak tahu kalau kau mencintaiku,"
goda Sada. "Tapi aku memang menyayangi
kucing itu!" Diraih lalu diusapnya leher
Maya seakan-akan sedang membelai kucing,
dan punggung gadis itu melengkung karena
nyaman. Sada mengira hampir bisa merasa-
kan lagi bulu di jari jemarinya.
"Kalau kau terus lakukan itu, kurasa aku
akan berubah menjadi si kucing," ujar Maya
sambil melamun.
"Aku yakin kelak ini bisa berguna." Nada
suara Sada terdengar praktis.
Maya menyeringai. "Itu sebabnya aku
menyukai Tribe," sahutnya. "Mereka tidak
keberatan kalau aku ini anak kembar, atau
roh si kucing merasuki diriku. Apa pun yang
berguna bagi mereka, baik adanya. Itu
menurutku. Aku tidak mau kembali pada
kehidupan di istana, atau kastil. Aku akan
tinggal bersama Tribe."
"Kita lihat apa pendapat Taku!"
Maya tahu Taku adalah guru yang tegas
dan tidak punya perasaan sentimentil, tapi ia
takut kalau gurunya itu terpengaruh dengan
kewajiban pada ayahnya sehingga cenderung
memperlakukannya dengan pengecualian. Ia
tak tahu mana yang lebih buruk: diterima
oleh Taku hanya karena ia adalah putri
Otori, atau ia ditolak karena kurang trampil.
Di satu saat ditemukan dirinya mengira kalau
Taku akan mengenyahkannya karena tak
mampu menolongnya; atau sebaliknya
kagum dengan segala yang bisa dilakukannya
dan semua potensi dirinya. Akhirnya akan
jadi sesuatu di antara dua hal: tidak terlalu
kecewa, tapi juga tidak terlalu memuaskan.
Muara berpasir terlalu dangkal untuk
dimasuki kapal, dan mereka turun dengan
menggunakan tali ke perahu nelayan yang
reot. Perahu-perahu itu sempit dan tidak
stabil; para awaknya tertawa ketika Maya
memegang erat-erat bagian pinggir atas dari
sisi perahu, serta berusaha menarik Sada ke
dalam percakapan cabul saat mengayuh ke
hulu, ke kota Maruyama.
Kastil berdiri di atas bukit kecil di atas
sungai dan kota yang menyebar di sekeliling-
nya. Bangunannya kecil dan indah, ber-
dinding putih dan beratap abu-abu, terlihat
mirip burung yang baru saja beristirahat,
sayapnya masih membentang, sinar matahari
mewarnainya dengan warna merah muda.
Maya mengenalnya dengan baik dan sering
tinggal di sana bersama ibu dan saudara-
saudaranya, tapi hari ini tujuannya bukan ke
kastil itu. Ia terus merendahkan pandangan
mata dan tidak bicara dengan siapa pun agar
tidak dikenali. Sesekali Sada berbicara
kepadanya dengan kasar, membentaknya agar
tidak berjalan dengan menggesekkan kaki ke
tanah. Maya menyahut, ya kak, tentu kak,
sambil berjalan tanpa mengeluh, walaupun
perjalanannya jauh dan bawaannya banyak.
Hari sudah hampir gelap saat mereka tiba di
rumah yang memanjang sampai ke sudut
jalan. Jendelanya dipalang dengan kayu, dan
atap rendahnya memanjang sampai ke
pinggiran atap. Di satu sisinya adalah toko
depan, yang kini tutup dan sepi. Dipasang ke
dinding satunya, ada gerbang besar. Dua
laki-laki berdiri di luar dengan bersenjata
pedang dan tombak lengkung panjang.
Sada bicara kepada salah satunya. "Apakah
mengira akan ada serangan, sepupu?"
"Ini dia masalah datang," sahutnya. "Apa
yang kau lakukan? Siapa anak itu?"
"Adikku, kau ingat padanya?"
"Pasti bukan Mai!"
"Bukan, bukan Mai, Maya. Kita masuk
saja dulu. Nanti akan kuceritakan. Taku ada
di Maruyama?" imbuhnya selagi gerbang
dibuka lalu mereka menyelinap masuk.
"Ya, dia datang beberapa hari lalu. Dia
bersama Lord Kono, dari Miyako, dan Lord
Sugita sedang menghibur mereka. Dia belum
mampir seperti biasa. Kami akan beri tahu
kalau kau dan adikmu ada di sini."
"Mereka kenal aku?" bisik Maya sewaktu
Sada meng-gandengnya melewati taman yang
gelap ke pintu masuk.
"Ya. Tapi mereka juga tahu kalau ini
bukan urusan mereka, jadi mereka takkan
bicara banyak."
Maya membayangkan bagaimana seorang
laki-lakiatau perempuanmenyamar se-
bagai prajurit, penjaga atau pelayan: mereka
mendekati Taku dengan komentar tentang
kuda atau makanan, lalu menambah se-
potong kalimat yang kedengaran sem-
barangan, lalu Taku bisa tahu....
"Mereka akan memanggilku apa?" ia ber-
tanya pada Sada seraya melangkah ringan ke
atas beranda.
"Memanggilmu? Dengan nama apa?"
"Apa nama rahasiaku yang hanya di-
ketahui Tribe?"
Sada tertawa hingga kehabisan suara.
"Mereka akan mengarangnya. Anak Kucing,
barangkali." Anak Kucing sudah kembali
malam ini. Maya hampir bisa mendengar
suara pelayanmemutuskan kalau pelayan
itu perempuanberbisik di telinga Taku
selagi membungkuk membasuh kaki Taku,
atau menuang sake untuknya, dan kemudian
... apa yang akan Taku lakukan?
Maya merasakan agak tahu: apa pun yang
akan terjadi tidak akan mudah.
Ia harus menunggu sampai dua hari.
Tidak ada waktu untuk bosan atau cemas,
karena Sada menyibukkannya dengan ber-
bagai latihan Tribe yang tak ada akhirnya,
karena kemampuan Tribe bisa selalu dikem-
bangkan, dan tak seorang pun, bahkan Muto
Kenji atau Kikuta Kotaro, menguasainya
dengan sempurna. Dan Maya hanyalah anak
kecil: waktunya masih banyak. Ia latihan ber-
diri tak bergerak dalam waktu lama, me-
regangkan dan melipat tubuh agar tetap
lemas, latihan mengingat dan mengamati,
bergerak cepat hingga nyaris tak terlihat dan
menggunakan sosok kedua. Maya lakukan
semua itu tanpa mengeluh karena sudah me-
mutuskan untuk mencintai Sada tanpa
syarat, dan berusaha membuatnya senang.
Di senja hari kedua, setelah malam men-
jelang dan mereka selesai makan, Sada mem-
beri isyarat pada Maya yang tengah menaruh
mangkuk di nampankarena di rumah ini
dia bukan lagi putri Lord Otori tapi gadis
termuda sehingga menjadi pelayan bagi
semua orang. Diselesaikan tugasnya, mem-
bawa nampan ke dapur, lalu melangkah
keluar beranda. Di ujung beranda, Sada ber-
diri sambil memegang lentera. Maya bisa
melihat wajah Taku, separuh terkena sinar,
separuh dalam kegelapan.
Maya menghampiri lalu berlutut di
hadapannya, tapi sebelumnya ia mengamati
reaksi di wajah Taku. Saat wajah itu terlihat
lelah, ekspresi wajah yang tegang, dan
bahkan kesal, hati Maya terpuruk. "Guru,"
bisiknya.
Taku mengerutkan dahi, dan memberi
isyarat pada Sada untuk mendekatkan
lentera. Maya merasakan panasnya lentera di
pipinya, lalu menutup mata. Cahaya lentera
berkedap-kedip di balik kelopak matanya.
"Pandang aku," kata Taku.
Mata Taku yang hitam, buram, menatap
lurus ke arahnya. Maya menahan tatapan
mata Taku tanpa berkedip, membuat
pikirannya kosong, tidak membiarkan
ekspresi yang menunjukkan kelemahannya
terlihat; dan di waktu yang bersamaan tidak
berani mencari-cari ada ekspresi apa di wajah
Taku. Tapi ia tak mampu mempertahankan
diri dari Taku: merasakan seolah ada
semacam bias sinar, atau pikiran, menembus
dirinya, melihat rahasia yang ia sendiri , tidak
tahu ada dalam dirinya.
"Uhhh," gerutu Taku, tapi Maya tak tahu
apakah gerutuan itu karena Taku setuju atau
terkejut. "Mengapa ayahmu mengirimmu
padaku?"
"Menurut Ayah aku dirasuki roh kucing,"
sahutnya pelan. "Ayah mengira Kenji
kemungkinan mewariskan ilmu Tribe
tentang hal-hal seperti ini kepadamu."
"Tunjukkan padaku."
"Aku tidak mau," sahut Maya.
"Biarkan aku melihat roh kucing ini, kalau
memang ada di sana." Suaranya mengandung
kecurigaan dan tak acuh. Maya bereaksi
dengan marah. Kemarahan menjalar ke
sekujur tubuhnya, langsung dan bukan
seperti manusia, membuat tubuhnya
melembut dan meregang, bulunya beriak;
telinganya menegak dan memamerkan gigi-
nya, bersiap menerkam.
"Cukup," kata Taku pelan, lalu
menyentuh pipi Maya dengan lembut.
Hewan itu menurut dengan sendirinya, lalu
mengeong.
"Kau tak memercayaiku," kata Maya datar.
Tubuhnya gemetar.
"Bila sebelumnya aku tak percaya, maka
kini aku percaya," sahutnya. "Sangat me-
narik. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kita
bisa memanfaatkannya? Pernahkah kau
berubah wujud hingga benar-benar menjadi
kucing?"
"Pernah, sekali," akunya. "Aku mem-
buntuti Sunaomi ke kuil Akane lalu
melihatnya kencing di celana!"
Taku mendengar sesuatu di balik ke-
beranian yang dibuat-buat itu. "Lalu?" tanya-
nya.
Maya tidak menjawab selama beberapa
saat; kemudian ia bergumam, "Aku tak mau
melakukannya lagi! Aku tidak menyukai
perasaan yang menyertainya."
"Tidak ada hubungannya kau suka atau
tidak," sahut Taku. "Jangan buang waktu.
Kau harus berjanji kalau kau hanya akan
melakukan apa yang Sada atau aku pinta,
tidak pergi sendiri sesuka hatimu, jangan
ambil resiko, jangan menyimpan rahasia pada
kami."
"Aku bersumpah."
"Ini bukan waktu yang tepat," kata Taku
dengan agak kesal pada Sada. "Aku sedang
berusaha mengawasi Kono, dan mengawasi
kakakku kalau-kalau dia bertindak yang tak
terduga. Tetap saja, bila Takeo memintanya,
kurasa sebaiknya aku menjaga agar Maya
tetap di dekatku. Kau bisa ikut ke kastil
denganku besok. Dandani dia seperti anak
laki-laki, tapi tinggallah di sini. Terserah kau
mau menjadi apa, tapi di sini ia harus tetap
sebagai anak perempuan. Sebagian besar
penghuni rumah ini sudah mengenalnya; dia
harus dilindungi sebaik-baiknya sebagai putri
Lord Otori. Aku akan memperingatkan
Hiroshi. Apa akan ada orang lain yang bisa
mengenalimu?"
"Tak seorang pun berani menatap
langsung padaku," tutur Maya. "Karena aku
anak kembar."
"Anak kembar cukup istimewa di kalangan
Tribe," tutur Taku. "Tapi di mana adikmu?"
"Dia di Hagi dan akan segera pergi ke
Kagemura." Mendadak rasa sakit hati mener-
jang diri Maya karena merindukan Miki,
Shigeko dan orangtuanya. Aku di sini seperti
anakyatim piatu, pikimya, atau orang yang
diasingkan. Mungkin aku akan menjadi seperti
Ayah, ditemukan di desa terpencil dengan lebih
banyak bakat yang dimiliki orang Tribe
lainnya.
"Sekarang pergi tidur," kata Taku tiba-
tiba. "Ada yang harus kubicarakan dengan
Sada."
"Guru." Maya membungkuk normal
dengan patuh dan mengucapkan selamat
malam kepada keduanya. Tidak lama setelah
ia masuk ke dalam rumah, seorang pelayan
mendekatinya lalu menyuruhnya menyiap-
kan alas tidur. Dibukanya lipatan matras lalu
membentangkan selimut, berjalan pelan
melewati kamar-kamar panjang dan rendah
rumah itu. Angin berhembus dan bersiul
melalui celahnya, membawa musim gugur,
tapi Maya tidak merasa kedinginan.
Didengarkannya suara-suara dari taman.
Mereka menyuruhnya pergi tidur dan ia
mematuhinya, tapi mereka tidak melarang-
nya untuk mendengarkan.
Maya mewarisi pendengaran tajam ayah-
nya, dan kini semakin peka. Ketika akhirnya
ia berbaring, dipasang telinganya baik-baik,
berusaha menyaring bisik-bisik dari para
gadis yang berbaring di sisi kanan dan
kirinya. Perlahan-lahan akhirnya mereka ter-
diam, suara pelan mereka berganti dengan
nyanyian terakhir serangga musim panas,
meratapi musim dingin yang akan datang
dan kematian mereka. Didengarnya kepakan
sayap burung hantu yang tenang sewaktu
terbang melewati taman, dan menghembus-
kan napas dengan amat perlahan hingga
nyaris tak terdengar. Sinar rembulan mem-
bentuk kisi-kisi di layar kertas; bulan
menarik darahnya dengan keras, membuat-
nya mengalir cepat melalui urat nadinya.
Di kejauhan Taku berkata, "Aku ajak
Kono kemari agar dia bisa melihat kesetiaan
di Maruyama kepada Otori. Aku cemas
Zenko telah membiarkannya percaya bahwa
Seishuu hendak memberontak, dan bahwa
wilayah Barat takkan berpihak kepada
Takeo."
"Bisakah Hiroshi dipercaya?" gumam
Sada.
"Kalau tidak, akan kugorok leherku,"
sahut Taku.
Sada tertawa. "Kau tidak akan bunuh diri,
sepupu."
"Kuharap aku tidak harus melakukannya.
Aku mungkin akan melakukannya karena
bosan harus bersama Lord Kono lebih lama
lagi."
"Maya akan menjadi hiburan yang
menyenangkan, bila kau takut merasa
bosan."
"Atau tanggung jawab lain yang tak bisa
kuhindari!"
"Kenapa kau terkejut saat menatap matan-
ya?"
"Aku mengharapkan tatapan anak
perempuan. Yang kulihat bukanlah seperti
anak perempuan: sesuatu yang tak berwujud,
menanti untuk menemukan wujudnya."
"Apakah arwah seorang laki-laki, atau
sesuatu yang berhubungan dengan kerasukan
si kucing?"
"Aku sungguh-sungguh tidak tahu.
Sepertinya berbeda. Maya unik kemung-
kinan sangat kuat."
"Dan berbahaya?"
"Mungkin. Terutama sekali bagi dirinya
sendiri."
"Kau lelah." Sesuatu dalam nada suara
Sada yang membuat tubuh Maya gemetar
dengan gabungan antara kerinduan dan
kecemburuan.
Sada berkata, lebih pelan lagi, "Mari, ku-
pijat dahimu."
Sesaat hening. Maya menahan napas.
Taku menghembuskan napas panjang. Ada
semacam kekuatan hasrat jatuh di taman
yang gelap, pada pasangan yang tidak
terlihat. Maya tidak tahan mendengarnya,
lalu menarik selimut hingga menutupi
kepalanya.
Lama setelah itu, sepertinya Maya men-
dengar langkah kaki di beranda. Taku bicara
dengan suara pelan, "Aku tidak meng-
harapkan itu!"
"Kita tumbuh dewasa bersama," sahut
Sada. 'Tidak perlu berarti apa-apa."
"Sada, tidak ada yang terjadi di antara kita
yang tidak berani apa-apa." Taku berhenti
sejenak seolah ingin berkata lagi, tapi lalu
berkata dengan singkat, "Aku akan me-
nemuimu dan Maya besok pagi. Bawa dia ke
kastil saat tengah hari."
Sada masuk ke kamar perlahan lalu ber-
baring di sebelah Maya. Berpura-pura ter-
tidur, Maya berbalik menghadapnya, meng-
hirup aroma tubuh itu bercampur dengan
aroma Taku masih teninggal di tubuhnya. Ia
tidak dapat memutuskan mana yang paling ia
cintai: ia ingin memeluk mereka berdua.
Pada saat itu Maya merasakan dirinya men-
jadi milik mereka selamanya.
***
Keesokan harinya Sada membangunkannya
pagi-pagi lain bersiap memotong rambutnya
yang panjang sebahu dan menariknya ke
belakang dan diikat ke atas, membiarkan
dahinya tidak dicukur, seperti laki-laki yang
masih di bawah umur.
"Kau bukanlah gadis yang cantik," kata
Sada seraya tertawa. "Tapi bisa menjadi anak
laki-laki yang tampan. Membentak sedikit
lagi, lalu katupkan bibirmu. Kau tidak boleh
kelihatan cantik! Nanti ada ksatria yang
membawamu kabur."
Maya mencoba mengatur tubuh agar ter-
lihat lebih mirip anak laki-laki, tapi rasa
senang, rambut dan pakaiannya yang masih
terasa asing membuat matanya berkilat dan
pipinya bersemu merah.
"Tenang," Sada menghardiknya. "Kau
jangan terlalu menarik perhatian. Kau adalah
salah seorang pelayan Lord Taku; pelayan
yang terendah derajatnya."
"Apa yang nanti harus kulakukan?"
"Sedikit sekali, kuharap. Beajarlah meng-
atasi rasa bosan."
"Seperti Taku," sahut Maya tanpa pikir
panjang.
Sada mencengkeram lengannya. "Kau
mendengarnya mengatakan itu? Apa lagi
yang kau dengar?"
Maya menjauhkan diri dari gadis itu.
Selama beberapa saat ia tidak membuka
mulut, tapi kemudian ia berkata, "Aku
dengar semuanya."
Sada tidak bisa menahan senyum. "Jangan
bilang pada siapa-siapa," gumamnya, dengan
nada mendukung. Ditariknya Maya lalu
dipeluknya. Maya balas memeluk, merasakan
panas tubuhnya, dan berharap Sada adalah
Taku.*
Sebagian laki-laki mengutamakan cinta, tapi
Muto Taku bukanlah salah satunya, atau ber-
hasrat ingin mengabdikan diri hanya untuk
orang yang dicintai. Menurutnya perasaan
berlebihan semacam itu aneh, bahkan men-
jijikkan, dan selalu menertawai orang yang
tergila-gila karena cinta, terang-terangan
membenci kelemahan mereka. Ketika ada
perempuan menyatakan terang-terangan
mencintainya, seperti yang sering terjadi,
Taku justru menjauhkan diri. Ia menyukai
perempuan, dan semua kesenangan yang bisa
dinikmati dari tubuh perempuan, menya-
yangi juga memercayai istrinya untuk meng-
atur rumah tangga, mengasuh anak-anak
dengan baik dan setia kepadanya, tapi
gagasan bersikap setia kepada istrinya tidak
pernah melintas di benaknya. Maka ingatan
yang tak mau pergi di benaknya tentang
keintiman yang terjadi tiba-tiba serta tidak
diharapkan bersama Sada mengganggu
pikirannya. Kejadian seperti itu belum
pernah dialaminya, hasrat yang begitu besar,
kepuasan yang begitu menusuk serta
sempurna; tubuh Sada yang sama tinggi dan
kuat dengan tubuhnya, hampir seperti tubuh
laki-laki namun sekaligus tubuh perempuan;
hasrat keperempuanan Sada yang menang-
gapi hasrat dirinya, berserah diri kepadanya.
Taku hampir tidak bisa tidur, hanya
menginginkan kehadiran Sada di sisinya.
Dan saat bicara dengan Sugita Hiroshi di
taman kastil di Maruyama, ia sulit ber-
konsentrasi pada apa yang sedang dibicara-
kan. Kita tumbuh dewasa bersama. Tidak
perlu berarti apa-apa, kata Sada waktu itu,
dan dia berubah dari teman, hampir seperti
adik, menjadi kekasih; dan Taku pun ber-
kata, tanpa tahu dari mana datangnya kata-
kata ini, Tak ada hal yang terjadi di antara
kita yang tidak berarti apa-apa.
Taku mengalihkan kembali perhatiannya
pada kawannya. Mereka sebaya, beranjak dua
puluh tujuh saat tahun baru nanti. Taku
berperawakan kuat dan sulit digambarkan,
wajah yang mudah berubah-ubah ekspresi
khas Muto, sedangkan Sugita Hiroshi di-
anggap tampan, setengah kepala lebih tinggi
dari Taku dan berbahu lebih bidang, dengan
kulit pucat dan bentuk tubuh gagah khas klas
ksatria. Saat masih kecil, mereka berdua
sering bertengkar dan saling bersaing
merebut perhatian Takeo, mereka pernah
menjinakkan kuda-kuda jantan bersama, dan
sejak itu terikat oleh hubungan persahabatan
yang amat dalam.
Saat itu masih pagi, cuaca tampak cerah di
musim gugur ini. Langit biru pucat terang
bak telur burung, matahari baru saja mulai
mengangkat kabut dari tum-pukan jerami
berwarna keemasan di sawah. Ini kesem-
patan pertama bagi kedua laki-laki ini bisa
bicara berdua sejnk kedatangan Taku ber-
sama Lord Kono. Mereka membicaraknn
tentang pertemuan yang akan datang dengan
Lord Otori dan Arai Zenko, yang diadakan
dalam beberapa minggu mendatang di
Maruyama.
"Takeo dan Lady Shigeko sudah harus di
sini pada bulan purnama berikutnya," kata
Hiroshi, "tapi kedatangan mereka agak ter-
tunda karena mereka ke Terayama untuk
ziarah ke makam Matsuda Shingen."
"Pasti Takeo sedih kehilangan dua guru-
nya di tahun yang sama. Dia belum bisa
melupakan kematian Kenji," komentar Taku.
"Kepergian Matsuda tidak semendadak
atau mengejutkan seperti kematian Kenji.
Kepala Biara kami sudah berusia lebih dari
delapan puluh tahun, waktu yang luar biasa
panjang. Dan beliau memiliki penerus yang
layak. Seperti yang dimiliki pamanmu pada
dirimu. Kau akan serasi dengan Lord Takeo
seperti layaknya Kenji."
"Aku merindukan ketrampilan dan
pengetahuan pamanku," aku Taku. "Tam-
paknya keadaan semakin rumit setiap
minggunya. Niat buruk kakakku, yang
bahkan aku sendiri tak bisa memahaminya;
Lord Kono dan tuntutan dari Kaisar;
penolakan Kikuta untuk berunding...."
"Selama aku di Hagi, kesibukan Takeo
tampak tidak seperti biasa," tutur Hiroshi
ragu-ragu.
"Baiklah, terlepas dari kesedihan dan
urusan-urusan negara ini, dia memiliki
kekhawatiran lain, kurasa," sahut Taku.
"Kehamilan Lady Otori, masalah putri-
putrinya."
"Terjadi sesuatu pada Lady Shigeko?" sela
Hiroshi. "Dia dalam keadaan sehat ketika
aku bertemu dengannya belum lama ini...."
"Sejauh yang kutahu, dia baik-baik saja.
Masalah si kembar," ujar Taku. "Maya ikut
bersamaku di sini; aku harus memperingat-
kanmu kalau-kalau kau mengenalinya."
"Di sini bersamamu?" ulang Hiroshi
merasa terkejut.
"Dia berpakaian seperti anak laki-laki.
Barangkali kau bahkan tidak memerhati-
kannya. Dia dirawat seorang perempuan
muda yang juga menyamar menjadi laki-laki,
kerabat jauh keluargaku: namanya Sada."
Sebenarnya ia tidak perlu menyebut nama
itu, namun ia tak mampu menahan diri: Aku
terobsesi, pikirnya.
"Zenko dan Hana akan datang," seru
Hiroshi. "Mereka pasti akan mengenalinya!"
"Hana mungkin saja. Tidak banyak yang
luput dari pandangannya."
"Memang benar," Hiroshi setuju. Mereka
berdua terdiam sesaat, kemudian tertawa di
saat bersamaan.
"Kau tahu," kata Taku, "orang bilang kau
tidak bisa melupakannya, dan itu sebabnya
kau tidak menikah!" Mereka sudah pernah
membicarakan masalah ini, tapi keingi-
ntahuan Taku bangkit oleh obsesi barunya
sendiri.
"Memang benar ada saat ketika aku sangat
bersemangat ingin menikah dengannya.
Kukira aku memujanya dan amat meng-
inginkannya menjadi bagian dari keluarga
ituayah kandungku, seperti yang kau tahu,
gugur dalam perang, dan paman beserta
putranya lebih memilih untuk mencabut
nyawa ketimbang menyerah pada Arai
Daiichi. Aku tidak memiliki keluargaku
sendiri; ketika Maruyama habis karena
gempa bumi, aku tinggal di kediaman Lord
Takeo. Tanah milik keluargaku dikembali-
kan ke wilayah kekuasaan itu. Aku dikirim ke
Terayama untuk mempelajari Ajaran Houou.
Saat itu aku masih sama bodoh dan
angkuhnya dengan para pemuda pada
umumnya. Kukira nantinya Takeo akan
mengangkatku sebagai putranya, terutama
ketika dia tidak punya anak laki-laki."
Hiroshi tersenyum mengejek dirinya sendiri
namun tanpa perasaan getir. "Jangan salah
paham. Aku tidak kecewa atau pun tertekan.
Aku melihat panggilan hidupku adalah
untuk melayani; aku senang menjadi
pengurus Maruyama dan mempertahankan-
nya untuk Lady Shigeko. Bulan depan dia
akan menerima wilayah itu; aku akan
kembali ke Terayama, kecuali kalau dia
memintaku berada di sini."
"Aku yakin Lady Shigeko akan mem-
butuhkanmusetidaknya selama satu atau
dua tahun. Tak perlu mengubur diri di
Terayama bak pertapa. Kau harus menikah
dan punya anak. Sementara itu untuk tanah,
Takeoatau Shigekoakan memberi apa
pun yang kau minta."
"Tidak semua yang kuminta," sahut
Hiroshi pelan, nyaris bicara pada dirinya
sendiri.
"Jadi kau masih tergila-gila pada Hana."
'Tidak, aku cepat pulih dari perasaan itu.
Hana memang cantik, tapi aku senang
kakakmu yang menjadi suaminya."
"Akan lebih baik bagi Takeo bila kau yang
menikah dengannya," ujar Taku, penasaran
apa lagi yang menahan Hiroshi tidak ingin
menikah.
"Mereka saling mengisi ambisi," Hiroshi
sepakat, dan dengan tangkasnya mengubah
topik pembicaraan. "Tapi kau belum
mengatakan alasan Maya berada di sini."
"Dia perlu dijauhkandari sepupu-
sepupunya yang kini berada di Hagi, dan dari
kembarannya. Dan harus ada yang meng-
awasinya terus-menerus, itu sebabnya Sada
ikut bersamanya. Aku harus selalu meng-
awasinya juga. Aku tak bisa menjelaskan
semua alasannya. Aku mengandalkanmu
untuk menutupi ketidakhadiranku dan
menghibur Lord Konodan sebelum aku
lupa, meyakinkan agar klan Seishuu benar-
benar setia pada Otori."
"Apakah anak itu dalam bahaya?"
"Dialah yang bahaya," sahut Taku.
"Tapi kenapa dia tidak datang secara ter-
buka, sebagai putri Lord Otori, dan tinggal
di sini seperti yang sudah sering dilakukan-
nya?"
Ketika Taku tidak segera menjawab,
Hiroshi berkata, "Pada dasarnya kau
memang suka intrik, akui saja!"
"Dia lebih berguna bila tidak dikenali,"
ujar Taku akhirnya. "Lagipula dia adalah
anak dari kalangan Tribe. Bila dia menjadi
Lady Otori Maya, maka hanya sampai
sebatas itu perannya; sedangkan di Tribe dia
bisa mengambil berbagai peran yang ber-
beda."
"Kurasa dia bisa melakukan semua tipuan
yang kau gunakan untuk menggodaku," kata
Hiroshi tersenyum.
"Tipuan-tipuan itu, sebagaimana kau me-
nyebutnya, pernah menyelamatkanku lebih
dari sekali!" sahut Taku dengan pedas.
"Selain itu, aku percaya Ajaran Houou juga
memiliki tipuan!"
"Para Guru Besar, seperti Miyoshi Gemba
dan Makoto, memiliki banyak kemampuan
yang kelihatannya supernatural, tapi sebenar-
nya itu adalah hasil dari latihan selama ber-
tahun-tahun dan pengendalian diri."
"Baiklah, kurang lebih sama dengan Tribe.
Kemampuan kami mungkin saja berasal dari
keturunan, tapi tidak ada artinya tanpa
latihan. Tapi apa para Guru Besarmu
berhasil membujuk Takeo agar tidak ber-
perang, baik di Wilayah Timur atau pun di
Wilayah Barat?"
"Ya, saat datang nanti dia akan mem-
beritahukan pada Lord Kono bahwa utusan
khusus kami dalam perjalanan ke Miyako
untuk menyiapkan kunjungan tahun depan."
"Apakah menurutmu kunjungan ini bijak-
sana? Bukankah Takeo justru menempatkan
diri di bawah kekuasaan jenderal baru ini, Si
Pemburu Anjing?"
"Tindakan apa pun yang menghindari
perang adalah tindakan yang bijaksana,"
sahut Hiroshi.
"Maaf, tapi ini adalah kata-kata aneh yang
keluar dari mulut seorang ksatria!"
"Taku, kita berdua menyaksikan ayah kita
mati di depan mata kepala kita..."
"Ayah, paling tidak, pantas mati! Aku tak-
kan lupa saat itu ketika kupikir Takeo
seharusnya membunuh Zenko..."
"Ayahmu bertindak dengan benar,
menurut keyakinan dan kode kehormatan-
nya," tutur Hiroshi tenang.
"Dia mengkhianati Takeo setelah ber-
sumpah untuk bersekutu dengannya!" seru
Taku.
"Tapi bila dia tidak bertindak seperti itu,
cepat atau lambat Takeo juga akan menye-
rangnya. Ini wajar dalam masyarakat kita.
Kita bertempur sampai bosan, dan setelah
beberapa tahun bosan dengan kedamaian lalu
berperang lagi. Kita menyembunyikan hasrat
haus darah dan hasrat untuk balas dendam
dengan kode etik kehormatan, yang kita
langgar sendiri ketika tampak pantas dilaku-
kan."
"Apa benar kau belum pernah membunuh
seorang pun?" tanya Taku sekonyong-
konyong.
"Aku diajari banyak cara untuk mem-
bunuh, dan belajar strategi perang sebelum
berumur sepuluh tahun, tapi aku belum
pernah bertarung dalam penempuran yang
sesungguhnya, dan aku belum pernah mem-
bunuh siapa pun. Kuharap takkan pernah."
"Saat nanti kalau kau di medan perang,
kau akan berubah pikiran," kata Taku. "Kau
akan mempertahankan diri layaknya semua
orang."
"Barangkali. Untuk sementara ini aku
akan lakukan apa pun untuk menghindari
perang."
"Aku khawatir kalau kakakku dan Kaisar
akan membawamu ke kancah peperangan.
Terutama karena kini mereka sudah
memiliki senjata api. Kau bisa pastikan kalau
mereka takkan tinggal diam sampai mereka
menjajal habis-habisan senjata baru mereka."
Ada gerakan di ujung taman, dan seorang
penjaga berlari menghampiri lalu berlutut di
depan Hiroshi.
"Lord Kono sudah datang. Lord Sugita!"
Dengan kehadiran si bangsawan, sikap
mereka berdua agak berubah: Taku menjadi
lebih waspada, tapi Hiroshi tampak lebih
terbuka dan ramah. Kono ingin melihat
berbagai kota dan pedesaan sehingga mereka
melakukan banyak ekspedisi. Si bangsawan
ditandu mewah yang berlapis emas, sedang-
kan kedua pemuda itu menunggang kuda,
anak-anak Raku. Cuaca musim gugur tetap
cerah dan terang, warna dedaunan semakin
hari semakin tua. Hiroshi dan Taku
menjelaskan kepada Kono tentang kekayaan
wilayah itu, pertahanan serta jumlah tentara,
kepuasan penduduknya, dan kesetiaan
mutlaknya pada Lord Otori. Si bangsawan
menerima semua informasi ini dengan sopan
santunnya yang tenang seperti biasa, hingga
perasaannya yang sebenarnya tidak diketahui.
Terkadang Maya turut dalam perjalanan-
perjalanan ini, menunggang kuda milik Sada,
sesekali menemukan dirinya berada cukup
dekat dengan Kono dan para penasihatnya
untuk mendengarkan apa yang mereka
gumamkan. Percakapannya kedengaran tidak
menarik dan sepele, tapi ia mengingat dan
mengulang kata demi kata untuk Taku
sewaktu datang ke rumah tempat ia dan Sada
tinggal, seperti yang Taku lakukan setiap dua
atau tiga hari sekali. Kadang-kadang Taku
datang larut malam, dan betapa pun larut-
nya, Taku selalu ingin bertemu Maya,
bahkan bila Maya sudah tertidur. Maya harus
bangun cepat, sesuai cara Tribe yang
mengendalikan kebutuhan tidur mereka
dengan cara yang sama untuk mengendalikan
semua kebutuhan dan hasrat mereka. Maya
harus mengerahkan seluruh tenaga dan
konsentrasinya untuk pertemuan malam hari
ini dengan gurunya.
Taku kerapkali kelelahan dan tegang,
kesabarannya hampir habis; pekerjaan ini
berjalan lambat dan banyak tuntutannya.
Maya ingin bekerja sama, tapi takut dengan
apa yang kemungkinan terjadi padanya.
Acapkali ia merindukan berada di rumahnya
di Hagi bersama ibu dan kakak juga adiknya.
Ia ingin menjadi anak-anak saja; ingin men-
jadi seperti Shigeko, tanpa kemampuan Tribe
dan tidak punya saudara kembar. Menjadi
anak laki-laki seharian telah menguras
tenaganya, tapi itu tidak ada apa-apanya di-
bandingkan dengan tuntutan yang baru.
Sebelumnya ia merasa pelatihan Tribe
mudah: menghilang, menggunakan sosok
kedua, tapi cara yang baru ini sepertinya jauh
lebih sulit dan lebih berbahaya. Maya tidak
membiarkan sikap Taku memengaruhi diri-
nya, kadang dengan wajah cemberut yang
dingin, kadang dengan kemarahan. Maya
mulai menyesali kematian si kucing dan
kerasukan roh hewan itu; ia memohon pada
Taku untuk menyingkirkannya.
"Aku tidak bisa," sahut Taku. "Yang bisa
kulakukan hanyalah membantumu belajar
mengendalikannya, dan menguasainya."
"Kau sudah terlanjur melakukannya," kata
Sada. "Kau harus menerimanya."
Kemudian Maya merasa malu dengan
kelemahannya. Dikiranya ia akan suka men-
jadi si kucing, tapi ternyata kucing itu lebih
kejam dan menakutkan dari yang ia perki-
rakan. Kucing itu ingin menariknya masuk
ke dunia lain, dunia tempat para hantu dan
arwah.
"Kucing itu bisa memberimu kekuatan,"
kata Taku. "Kekuatan itu sudah ada; kau
harus meraih dan memanfaatkannya!"
Tapi meski berada di bawah pengawasan
dan bimbingan Taku hingga Maya sudah
terbiasa dengan roh yang hidup dalam
dirinya, tapi ia tetap tidak bisa melakukan
apa yang Taku harapkan: mengambil bentuk
kucing itu lalu memanfaatkannya.*
Bulan purnama di bulan kesepuluh semakin
dekat, dan di mana-mana persiapan Perayaan
Musim Gugur telah dimulai. Kegembiraan
kian bertambah tahun ini dengan kenyataan
bahwa Lord Otori sena putri sulungnya, pe-
waris Maruyama, Lady Shigeko, akan meng-
hadiri perayaan. Penduduk kota turun ke
jalan setiap malam dengan pakaian berwarna
cerah dan sandal baru sambil bernyanyi, me-
lambaikan tangan di atas kepala. Maya sudah
tahu kalau ayahnya dikenal banyak orang,
bahkan dicintai, tapi tak sepenuhnya me-
nyadari sampai tahap apa hingga mendengar-
nya sendiri dari mulut orang-orang yang saat
ini berbaur dengan dirinya. Tersiar juga
berita bahwa wilayah ini secara resmi akan
dipersembahkan kepada Shigeko karena
sekarang usianya sudah mencukupi.
"Memang benar," kata Taku pada Maya
saat ia menanyakannya. "Hiroshi sudah
membicarakannya denganku. Shigeko akan
mengganti nama dan sejak saat ini dikenal
sebagai Lady Maruyama."
"Lady Maruyama," ulang Maya. Ke-
dengarannya seperti legenda, nama yang
sering didengar, dari Chiyo, dari Shizuka,
dari para penyanyi balada yang menyanyikan
dan menceritakan kisah-kisah Otori di sudut
jalanan dan tepi sungai.
"Ibuku sekarang yang memimpin Tribe,
Lady Shigeko kelak akan memimpin Tiga
Negara; sebaiknya kau berubah menjadi anak
perempuan lagi sebelum usiamu semakin
bertambah!" Taku menggodanya.
"Aku tidak tertarik dengan Tiga Negara,
tapi aku ingin memimpin Tribe!" sahut
Maya.
"Kau harus tunggu sampai aku mati!"
Taku tertawa.
"Jangan bilang begitu!" Sada memper-
ingatkannya, seraya menyentuh lengannya.
Taku langsung berpaling dan menatap Sada
dengan pandangan yang membuat hati Maya
berdebar sekaligus cemburu. Ketiganya
berada di kamar kecil di ujung rumah Tribe.
Maya tak menduga Taku datang begitu
cepatia sudah di sana sejak kemarin
malam.
"Lihat saja, aku tidak bisa jauh darimu,"
kata Taku sewaktu Sada mengungkapkan
rasa terkejutnya karena Taku datang cepat.
Sada yang tak bisa menyembunyikan rasa
senang, tidak bisa menahan diri untuk terus
menyentuh Taku.
Malam itu dingin dan terang. Empat hari
sebelum pumama, bulan sudah makin
membesar dan menguning. Meski udara
dingin, daun jendela tetap terbuka; mereka
bertiga duduk berdekatan di dekat tungku
batu bara, selimut tebal menyelimuti tubuh
mereka. Taku minum sake, tapi baik Sada
maupun Maya tak suka rasanya. Satu lentera
kecil kalah dengan gelapnya ruangan itu, tapi
taman penuh sinar bulan dan bayang-bayang
pekat.
"Lalu ada kakakku," bisik Taku pada Sada,
tidak lagi berkelakar, "yang percaya kalau
sudah menjadi haknya untuk memimpin
Tribe, sebagai kerabat tertua Kenji."
"Aku takut ada juga orang lain yang tidak
setuju Shizuka menjadi Ketua Muto.
Perempuan belum pernah memimpin
keluarga itu; orang-orang tidak suka bila
tradisi diubah. Mereka menggerutu kalau
tindakan ini menying-gung dewa-dewa.
Bukannya menginginkan Zenko; mereka
lebih memilihmu, pastinya, tapi penunjukan
ibumu telah menyebabkan perpecahan."
Maya mendengarkan dengan cermat,
tanpa bicara, sadar akan hawa panas di satu
sisi wajahnya, dan udara dingin di sisi wajah
yang satunya lagi. Dari kota terdengar musik
dan nyanyian, tabuhan genderang dengan
irama tegas, disela dengan teriakan-teriakan
parau.
"Aku mendengar satu desas-desus hari
ini," kata Sada. "Kikuta Akio terlihat di
Akashi. Dia berangkat ke Hofu dua minggu
lalu."
"Sebaiknya kita segera kirim orang ke
Hofu," kata Taku. "Dan cari tahu mau ke
mana dia dan apa tujuannya. Apakah dia
bepergian seorang diri?"
"Imai Kazuo bersamanya, dan putranya."
"Putra siapa?" Taku duduk tegak. "Bukan
putra Akio, kan?"
"Sepertinya ya, anak laki-laki berusia
sekitar enam belas tahun. Mengapa kau
begitu kaget?"
"Kau tidak mengenal siapa anak itu?"
"Dia adalah cucu Muto Kenji, semua
orang tahu itu," sahut Sada.
"Tidak ada lagi?"
Sada menggeleng.
"Kurasa itu adalah rahasia Kikuta,"
gumam Taku. Lalu sepertinya dia ingat akan
kehadiran Maya.
"Suruh anak itu tidur," katanya pada Sada.
"Maya, tidurlah di kamar pelayan,"
perintah Sada. Sebulan lalu ia pasti akan
protes, tapi ia sudah belajar mematuhi Sada
dan Taku dalam segala hal.
"Selamat malam," gumamnya, lalu bangkit
berdiri.
"Tutup jendelanya sebelum pergi," kata
Taku. "Udara semakin dingin."
Sada berdiri membantu. Jauh dari api
membuat Maya kedinginan, dan begitu
berada di kamar pelayan ia justru merasa
lebih dingin. Semua orang sepertinya sudah
tidur; Maya menemukan tempat di sela dua
orang gadis dan merangkak melewati mereka.
Di sini, di rumah Tribe semua orang tahu
kalau ia anak perempuan; hanya di dunia
luarlah ia harus tetap menyamar sebagai anak
laki-laki. Tubuh Maya gemetar; ingin men-
dengar apa yang Taku katakan, ingin
bersamanya dan Sada: Maya memikirkan
bulu kucing yang tebal dan halus menye-
limuti dirinya, menghangatkan tubuhnya,
dan gemetar tubuhnya berubah menjadi
sesuatu yang lain, riak kekuatan menjalar ke
sekujur tubuhnya karena si kucing meregang-
kan otot-ototnya dan hidup lagi,
Maya menyelinap dari balik selimut dan
melangkah tanpa bersuara dari kamar itu,
sadar akan bola matanya yang membesar dan
pandangannya yang tajam, mengingat bagai-
mana dunia itu penuh dengan gerakan kecil
yang belum pernah diperhatikannya, men-
dengarkan dengan agak takut suara-suara
hampa para arwah. Ia sudah berada separuh
jalan ke gang selasar ketika ia sadar tengah
bergerak melayang di atas permukaan tanah,
lalu menjerit keras ketakutan.
Aku tidak bisa membuka pintunya, pikir
Maya, tapi roh kucing lebih tahu, dan me-
lompat ke jendela, melayang melewatinya,
melambung menyeberangi beranda dan me-
masuki ruangan tempat Sada dan Taku
berangkulan. Maya berpikir akan menam-
pakkan diri kepada mereka, kalau Taku akan
merasa senang dan memujinya. Ia ingin ber-
baring di antara mereka.
Sada bicara dengan nada setengah malas,
merangkum percakapan sebelumnya, kata-
kata yang paling mengguncang diri Maya
daripada semua yang pemah dialaminya, tapi
bergema dalam roh kucing yang belum mati.
"Bocah itu benar-benar putra Takeo?"
"Ya, dan menurut ramalan, akan menjadi
saru-satunya orang yang bisa membawa
kematian padanya."
Maya mengetahui keberadaan kakak laki-
lakinya, dan ancaman terhadap ayahnya. Ia
berusaha tetap diam tapi tidak bisa menahan
lolongan ketakutan dan putus asa yang
memaksa keluar dari tenggorokannya. Di-
dengarnya Taku berseru, "Siapa di sana?"
dan mendengar teriakan kaget Sada, dan ia
melompat menerobos kasa dan keluar ke
taman seolah bisa lari selama-lamanya, jauh
dari segalanya. Tapi ia tidak bisa berlari dari
suara-suara arwah yang bergemerisik di
telinganya yang berdiri tegak dan merasuk ke
dalam tulangnya yang rapuh dan cair.
Di mana Penguasa kami?*
Otori Takeo dan Arai Zenko tiba di
Maruyama selang beberapa jam, sehari
sebelum bulan purnama. Takeo datang dari
Yamagata dan membawa sebagian besar
orang istana Otori, termasuk Miyoshi Kahei
dan adiknya Gemba, satu iring-iringan kuda
membawa catatan-catatan administrasi yang
harus ditangani saat ia berada di wilayah
Barat, sejumlah besar pengawal, dan putri
sulungnya, Udy Shigeko. Zenko didampingi
pengawal yang sama banyaknya, kuda-kuda
pengangkut keranjang berisi hadiah-hadiah
mewah dan pakaian-pakaian mahal, burung
rajawali dan anjing kecil milik Lady Arai,
serta Lady Arai sendiri, di dalam tandu yang
diukir dan dihias dengan indah.
Kedatangan para pemimpin dengan iring-
iringan mereka menutupi jalan dan me-
menuhi rumah penginapan membuat pen-
duduk kota gembira. Sebulan terakhir ini
mereka telah menambah persediaan beras,
ikan, kedelai, sake dan makanan khas daerah
mereka, dan kini berharap bisa mendapat
keuntungan besar. Musim panas bermurah
haii menghasilkan panen berlimpah;
Maruyama segera diserahkan pada pewaris
perempuannya: banyak yang harus diraya-
kan. Di mana-mana umbul-umbul berkibar
tertiup angin, menggambarkan bukit bulat
Maruyama bersama bangau Otori, dan
jurumasak saling berlomba menciptakan
santapan berbentuk bulat untuk meng-
hormati bulan purnama.
Takeo melihat itu semua dengan gembira.
Maruyama adalah wilayah yang amat di-
sayanginya karena di sinilah ia menghabiskan
bulan-bulan pertama setelah pernikahannya
dan mulai mempratikkan semua yang telah ia
pelajari dari Lord Shigeru tentang pe-
merintahan dan pertanian. Wilayah ini nyaris
hancur tersapu badai dan gempa bumi di
tahun pertama pemerintahannya. Kini,
setelah enam belas tahun berlalu, wilayah ini
menjadi kaya dan damai; perdagangan maju
pesat, seni berkembang, anak-anak makan
berkecukupan, semua luka bekas perang
tampak telah lama pulih, dan Shigeko akan
mengambil alih wilayah ini lalu memerintah
berdasarkan hak dan kewajibannya. Takeo
tahu putrinya layak mendapatkannya.
Ia harus terus mengingatkan dirinya
sendiri kalau ia berada di sini untuk
menemui dua laki-laki yang mungkin akan
merampas wilayah ini dari Shigeko.
Salah satunya, Lord Kono, diberi
penginapan seperti dirinya di dalam kastil.
Zenko tinggal di kediaman yang paling
bergengsi dan mewah di balik dinding kastil,
yang dulunya adalah kediaman Sugita
Haruki, pengawal senior wilayah tersebut
yang bersama putranya memilih bunuh diri
ketimbang setuju untuk menyerahkan kota
ini kepada Arai Daiichi. Takeo penasaran
apakah Zenko menyadari sejarah kesetiaan
dari rumah itu, dan berharap kalau laki-laki
itu dipengaruhi arwah dari para mendiang
yang setia.
Sebelum makan malam, saat Takeo harus
bertemu dengan musuh-musuh potensialnya
ini, dipanggilnya Hiroshi untuk bicara ber-
dua. Pemuda itu tampak tenang dan
waspada. Setelah membahas prosedur dan
upacara untuk keesokan harinya, Takeo
mengucapkan terima kasih atas kerja keras-
nya. "Kau telah bertahun-tahun mengabdi
pada keluargaku. Kami harus memberimu
imbalan. Kau ingin tinggal di wilayah Barat?
Akan kucarikan tanah dan bangunan untuk-
mu serta seorang istri. Aku sudah memper-
timbangkan cucu Lord Terada, Kaori. Dia
gadis yang amat baik, kawan baik putriku."
"Untuk memberiku tanah di Maruyama,
berarti akan mengambilnya dari orang lain,
atau dari Lady Shigeko," sahut Hiroshi. "Aku
sudah bilang pada Taku: aku akan tetap di
sini selama dibutuhkantapi keinginanku
yang sebenarnya yaitu diijinkan mengundur-
kan diri ke Terayama dan mengikuti Ajaran
Houou."
Takeo menatapnya tanpa langsung men-
jawab. Tatapan mata Hiroshi beradu
pandang dengannya lalu berpaling ke arah
lain. "Dan untuk pernikahan... aku berterima
kasih atas perhatian Anda, tapi aku sungguh-
sungguh tak ingin menikah, dan aku tidak
punya apa-apa untuk diberikan pada seorang
istri."
"Keluarga mana pun di Tiga Negara akan
menyambutmu dengan gembira sebagai
menantu. Kau kurang menghargai dirimu.
Bila kau tidak suka pada Terada Kaori, biar
kucarikan gadis lain. Apakah ada gadis lain?"
"Tidak ada," sahut Hiroshi.
"Kau tahu betapa besar rasa sayang
keluargaku padamu," lanjut Takeo. "Kau
sudah seperti kakak laki-laki bagi ketiga
putriku; andai usia kita tidak terlalu dekat
jaraknya, aku pasti akan mengangkatmu
menjadi putraku."
"Kumohon, Lord Takeo, jangan
diteruskan," kata Hiroshi dengan nada
memohon. Wajahnya mulai memerah.
Berusaha menyembunyikan rasa tertekannya
dengan tersenyum. "Anda bahagia dalam
perkawinan hingga ingin kami semua
memiliki keadaan yang sama! Tapi aku ter-
panggil ke jalan lain. Satu-satunya per-
mintaanku adalah diijinkan mengikuti jalan
itu."
"Aku tidak akan menentang keinginanmu
itu!" sahut Takeo, lalu memutuskan untuk
menghentikan masalah pernikahan ini
sementara waktu. "Tapi aku punya satu
permintaan, yaitu mendampingi kami ke
ibukota tahun depan. Seperti yang kau tahu,
aku mengatur kunjungan damai ini atas
permintaan para Guru Besar Ajaran Houou.
Aku ingin kau ambil bagian dalam kun-
jungan ini."
"Ini merupakan kehormatan bagiku,'
sahut Hiroshi. "Terima kasih."
"Shigeko juga akan ikut denganku atas
saran para Guru Besar. Kau harus
melindunginya, seperti yang sudah biasa kau
lakukan."
Hiroshi membungkuk tanpa bicara.
"Putriku mengusulkan agar kita membawa
kirin, yang akan menjadi hadiah yang tak ada
bandingnya untuk Kaisar."
"Anda ingin memberikan kirin!" seru
Hiroshi.
"Aku rela memberikan segalanya bila itu
mempertahankan kedamaian di negeri ini,"
sahut Takeo.
Bahkan Shigeko? Keduanya tidak me-
nyuarakan kata-kata itu, namun kata-kata itu
bergema di benak Takeo. Ia tidak tahu
apakah sudah bisa menjawab atau belum.
Sesuatu dari perbincangan ini pasti telah
membuatnya waspada sehingga di saat ia
tidak disibukkan oleh Lord Kono, Zenko dan
Hana, ditemukan dirinya lebih memerhati-
kan Hiroshi dan putrinya saat makan malam.
Mereka berdua, entah mengapa, lebih
pendiam, dan sedih, nyaris tidak saling bicara
atau bertatapan. Takeo tidak bisa meng-
ungkapkan ada perasaan khusus apa di antara
mereka berdua; dibayangkannya hati Shigeko
tidak tersentuh. Tapi tentu saja mereka
berdua sangat mahir menyembunyikan
perasaan masing-masing.
Makan malam berlangsung resmi dan
anggun, dengan menu khas musim gugur di
wilayah Barat: jamur pohon pinus, kepiting
dan udang kecil, gurih dan gating, chestnuts
and kacang ginko, disajikan di atas nampan
berpernis dan tembikar berwarna coklat
muda kekuningan pucat dari Hagi. Kaede
telah membantu mengembalikan kediaman
itu pada keindahan aslinya: tikar berwarna
hijau keemasan dan beraroma manis; lantai
dan balok-balok penyangga berkilau dengan
hangat; di belakangnya berdiri kasa ber-
hiaskan burung dan bunga musim gugur,
burung gelatik dengan semak semanggi,
burung puyuh dengan krisan. Takeo
bertanya-tanya bagaimana pendapat Kono
tentang semua yang dilihatnya di sini, dan
bagaimana bila dibandingkan dengan istana
Kaisar.
Takeo meminta maaf atas ketidakhadiran
istrinya, menjelaskan tentang kehamilan
istrinya, dan ingin tahu apakah Zenko dan
Hana kecewa dengan kabar ini karena akan
menunda rencana pengangkatan kedua putra
mereka.
Takeo seakan melihat perasaan tidak suka
sesaat sebelum Hana mulai mengucapkan
selamat yang berlebihan, mengungkapkan
kebahagiaannya, dan berharap kakaknya
mendapatkan anak laki-laki. Takeo, pada
gilirannya, dengan berhati-hati memuji
Sunaomi dan Chikarayang tidaklah sulit
dilakukan karena ia dengan tulus memang
menyayangi kedua anak itu.
Kono berkata dengan sopan, "Aku sudah
menerima surat dari Miyako. Aku paham
Anda akan mengunjungi Kaisar tahun
depan."
"Bila beliau berkenan menerimaku, ituiah
tujuanku," sahut Takeo.
"Kurasa beliau akan menerima Anda.
Semua orang ingin tahu tentang Anda.
Bahkan Lord Saga Hideki telah meng-
ungkapkan keinginannya untuk berjumpa
dengan Anda."
Takeo menyadari kalau Arai Zenko
memerhatikan tiap kata dengan tetap
menunduk. Dan bila mereka menyerang lalu
membunuhku di sana, Zenko akan menunggu
di wilayah Barat, mendahului restu sang
Kaisar...
"Lord Saga saat ini tengah memikirkan
semacam olah-raga atau pertandingan. Beliau
menulis surat kepadaku bahwa ketimbang
menumpahkan darah ribuan orang, beliau
lebih suka bertemu Lord Otori dalam per-
tandinganberburu anjing, mungkin. Itu
kegemarannya."
Takeo tersenyum. "Lord Saga tidak
mengetahui masalah-masalah kecil kami.
Beliau tidak tahu kalau tanganku yang cacat
menghambatku untuk menarik busur."
Untungnya, Takeo tidak bisa menahan untuk
berpikir, karena aku tidak mahir memanah.
"Baiklah, mungkin ada pertandingan yang
lain. Keadaan istri Anda yang meng-
haruskannya berdiam diri di rumah jadi tidak
memungkinkannya mendampingi Anda?"
"Begitulah. Tapi putriku akan ikut."
Shigeko mengangkat kepala lalu melihat ke
arah ayahnya. Tampak mata mereka bertemu
lalu dia tersenyum kepada ayahnya.
"Lady Shigeko bertunangan?" tanya Kono.
"Belum, belum," jawab Takeo.
"Lord Saga baru saja menduda." Suara
Kono terdengar dingin dan datar.
"Aku turut berduka." Takeo ingin tahu
apakah ia bisa tahan menyerahkan putri
sulungnya pada orang seperti Lord Saga
namun bisa menjadi persekutuan yang baik,
dan bila itu bisa memastikan kedamaian di
Tiga Negara...
Shigeko angkat bicara, suaranya terdengar
jernih dan tegas. "Aku tak sabar ingin ber-
jumpa Lord Saga. Mungkin beliau akan
menerimaku sebagai pengganti ayahku dalam
pertandingan apa pun nantinya."
"Lady Shigeko amat mahir memanah,"
imbuh Hiroshi.
Takeo mengingat dengan takjub kata-kata
Gemba: Akan ada semacam pertandingan di
Miyako... putrimu sebaiknya ikut. Dia harus
menyempurnakan keahlian menunggang kuda,
memanah... Bagaimana Gemba bisa tahu hal
ini?
Takeo memandang ke seberang ruangan,
ke arah Gemba yang duduk agak menjauh di
sebelah adiknya, Kahei. Gemba tidak
melihatnya, tapi ada senyum tipis tersung-
ging di wajah montoknya. Kahei terlihat
lebih tegas, menyembunyikan ketidak-
setujuannya.
Ini memperkuat bukti anjuran para Guru
Besar, pikir Takeo cepat. Aku akan datang ke
Miyako. Aku akan terima tantangan Saga, apa
pun itu. Kami akan selesaikan masalnh tanpa
harus berperang.
Tampaknya Kono sama terkejutnya
dengan Takeo, walaupun dengan alasan lain.
"Aku tidak menyadari kalau perempuan di
Tiga Negara begitu berbakat, dan pembe-
rani," katanya pada akhirnya.
"Seperti halnya Lord Saga, mungkin Anda
belum mengenal kami dengan baik," sahut
Shigeko. "Ini semakin menambah alasan
mengapa kami harus berkunjung ke ibukota,
agar Anda semakin memahami kami."
Shigeko berbicara dengan sopan, namun juga
tak bisa menghilangkan kesan berkuasa yang
ada di balik kata-katanya. Dia tidak mem-
perlihatkan rasa tidak suka bertemu dengan
putra orang yang pernah menculik ibunya,
atau kelihatan terintimidasi dengan ke-
hadirannya. Rambut panjangnya tergerai di
bahu; punggungnya tegak lurus, kulitnya
nyaris bercahaya dengan jubah wama kuning
pucat dan emas yang dikenakannya, dengan
dedauan maple yang cerah. Takeo ingat saat
pertama kali melihat Lady Maruyama
Naomi: menurutnya perempuan itu seperti
Jato, pedangnya, kecantikan yang menyem-
bunyikan kekuatan. Kini dilihatnya kekuatan
yang sama pada putrinya, dan merasa agak
lega. Apa pun yang terjadi, ia telah memiliki
pewaris. Ini memastikan bahwa Tiga Negara
akan tetap bersatu bila diwariskan kepada-
nya.
"Aku sungguh tidak sabar menantinya!"
seru Kono. "Kuharap aku bisa dibebaskan
dari keramahan Lord Otori untuk kembali ke
Miyako sebelum Anda tiba di sana, dan
memberitahukan kepada Yang Mulia Kaisar
tentang semua yang kudapatkan di sini." Dia
membungkuk dan bicara dengan ber-
semangat, "Aku bisa meyakinkan bahwa
semua taporanku akan berpihak kepada
Anda."
Takeo membungkuk sedikit tanda setuju,
ingin tahu seberapa banyak kata-kata ini
diucapkan dengan tulus, seberapa banyak
pujiandan niat buruk apa yang direnca-
nakan Kono dan Zenko. Berharap Taku tahu
lebih banyak, dan ingin tahu ada di mana dia
sekarang, mengapa dia tidak hadir saat santap
malam. Apakah Zenko tersinggung atas
kehadiran dan pengawasan Taku sehingga
sengaja tidak mengundang adiknya? Dan ia
pun cemas ingin mendengar kabar tentang
Maya. Ia tak dapat menahan diri untuk
berpikir kalau ketidakhadiran Taku tak ber-
kaitan dengan putrinya itu: kalau Maya
dalam masalah; atau melarikan diri....
Disadarinya kalau pikirannya melayang jauh,
dan tak mendengarkan kalimat terakhir Lord
Kono. Dipaksa dirinya berkonsentrasi pada
saat ini.
Tampaknya tidak ada lagi alasan untuk
menahan bangsawan itu; tentu saja, saat ini
merupakan waktu yang tepat untuk
mengirimnya pulang dengan pikiran yang
penuh dengan kesejahteraan wilayah ini,
kesetiaan klan Seishuuserta keindahannya,
karakter dan kecantikan putri sulungnya.
Tapi Takeo lebih suka mendengarnya dari
Taku, detail mengenai kunjungan singkat
Kono di wilayah Barat, hubungan bangsawan
itu dengan Zenko dan Hana.
Keramaian perayaan berlanjut hingga larut
malam: pemusik memainkan kecapi tiga
senar dan harpa, sementara dari kota
terdengar genderang dan nyanyian. Takeo
tidur tidak nyaman, pikirannya masih penuh
dengan kecemasan atas ketiga putrinya,
Kaede yang sedang mengandung. Saat
bangun pagi-pagi, merasakan nyeri di tangan
dan rasa sakit menjalari sekujur tubuhnya. Ia
meminta Minoru dibangunkan, dan selagi
minum teh ia mengingat-ingat apa saja yang
ia katakan semalam, memeriksa kalau segala-
nya telah dicatat dengan benar karena
Minoru ditempatkan di balik kasa
semalaman. Karena Kono diijinkan pergi,
banyak hal yang harus disiapkan.
"Apakah Lord Kono bepergian lewat laut
atau darat?" tanya Minoru.
"Lewat laut, bila ingin tiba sebelum
musim dingin," sahut Takeo. "Pasti salju
sudah turun di Jajaran Awan Tinggi: dia
takkan tiba di sana sebelum perbatasan
ditutup. Dia bisa saja lewat darat menuju
Hofu dan naik kapal laut dari sana."
"Jadi beliau akan melakukan perjalanan
bersama Lord Otori sampai Yamagata?"
"Ya, kurasa bagusnya begitu. Kita harus
tunjukkan satu pemandangan lagi padanya.
Sebaiknya kau siapkan Lady Miyoshi."
Minoru membungkuk hormat.
"Minoru, kau selalu hadir dalam per-
temuanku dengan Lord Kono. Sikapnya
padaku semalam sepertinya sedikit berubah,
bagaimana pendapatmu?"
"Sikapnya seperti hendak berbaikan,"
sahut Minoru. "Beliau pasti mengamati
kepopuleran Lord Otori, pengabdian dan
kesetiaan rakyat di sini. Di Yamagata aku
yakin Lord Miyoshi akan menjelaskan
ukuran dan kekuatan bala tentara kita. Lord
Kono pasti membawa kabar kepada Kaisar
dengan keyakinan bahwa Tiga Negara tak
mudah ditaklukkan, dan...."
"Teruskan," sela Takeo.
"Aku tidak berhak untuk mengatakannya,
tapi Lady Shigeko belum menikah, dan Lord
Kono pastinya akan lebih memilih untuk
merundingkan pernikahan ketimbang me-
mulai perang yang tidak bisa dimenangkan.
Apabila beliau yang akan menjadi perantara,
maka beliau harus mendapat kepercayaan
dan persetujuan ayah calon mempelai
perempuan."
"Baiklah, kita akan terus menyanjung dan
berusaha membuatnya terkesan. Ada kabar
dari Taku? Aku menantikannya tadi malam."
"Dia mengirim permintaan maaf kepada
kakaknya, mengatakan bahwa dia sedang
kurang sehathanya itu," sahut Minoru.
"Apa aku harus menghubunginya?"
"Tidak perlu, pasti ada alasan lain dengan
ketidakhadirannya. Selama kita tahu dia
masih hidup, maka semuanya baik-baik saja."
"Tentunya tak ada orang yang akan
menyerang Lord Kono, di Maruyama sini?"
"Taku telah menyinggung banyak pihak
dengan mengabdi padaku," tutur Takeo.
"Tak satu pun dari kita yang benar-benar
aman."
***
Panji-panji Klan Maruyama, Otori serta
Seishuu berkibaran di atas lapangan kuda di
depan kastil. Parit yang mengelilinginya
penuh dengan perahu-perahu berlambung
datar yang ditumpangi para penonton.
Anjungan dari sutra didirikan bagi kelompok
masyarakat dengan klas lebih tinggi, dan
lambang berhias rumbai bergelanmngan dari
atap dan dari tiang pancang yang ditanam di
sekelilingnya. Takeo duduk di atas mimbar
yang ditinggikan di salah satu pavilion ini,
bantal dan karpet bertebaran di lantai. Kono
di sebelah kanan, dan Zenko di sebelah kiri,
dan di belakang Zenko, Hana.
Hiroshi berada di depan mereka dengan
menunggang kuda abu-abu pucat dengan
surat dan ekor hitam. Kuda pemberian
Takeo bertahun-tahun lalu itu menunggu
diam tak bergerak bak patung. Di belakang-
nya, tanpa kuda, memegang kotak-kotak
berpernis, berdiri para tetua klan, semua
mengenakan jubah tebal berhias bordiran
emas, dan bertopi hitam. Di dalam kotak-
kotak terdapat harta kekayaan wilayah ini,
dan gulungan berisi silsilah keluarga meng-
gambarkan silsilah Shigeko melalui semua
perempuan Maruyama.
Kaede seharusnya berada di sini, pikir
Takeo dengan rasa menyesal; rindu berjumpa
dengan istrinya untuk menceritakan
pemandangan ini.
Takeo turut merencanakan upacara ini
semuanya dilakukan Hiroshi karena ini
merupakan ritual kuno Maruyama yang
belum dilaksanakan lagi sejak Lady Naomi
mewarisi wilayah ini. Takeo memindai
kerumunan orang, ingin tahu di mana
Shigeko, dan kapan putrinya akan muncul.
Di antara kerumunan perahu, tiba-tiba
dilihatnya Taku, tidak berpakaian resmi
seperti kakaknya, Zenko, tapi berpakaian
pedagang biasa yang lusuh. Di sampingnya
berdiri seorang pemuda tinggi dan seorang
lagi yang tampak amat tidak asing. Butuh
beberapa waktu bagi Takeo untuk menyadari
kalau orang itu adalah putrinya, Maya.
Takeo merasa takjubkalau ternyata
Taku mengajak putrinya datang dengan
menyamar, kalau ternyata ia tidak menge-
nalinyadiikuti dengan rasa lega yang
berdesir cepat kalau putrinya masih hidup
dan baik-baik saja. Maya tampak lebih kurus,
agak lebih tinggi, bola matanya lebih jelas
dengan wajah tajamnya. Seorang lagi pastilah
Sada, pikirnya, meskipun dia menyamar
hingga hampir tidak dikenali. Taku pasti tak
ingin meninggalkan Maya karena bila tidak,
dia pasti datang sebagai dirinya sendiri. Taku
pasti tahu ia akan mengenali mereka bertiga,
saat orang lain tak ada yang tahu. Pesan apa
yang dibawanya? Ia harus bertemu mereka: ia
akan temui mereka malam ini.
Perhatiannya tertuju kembali ke upacara
setelah mendengar derap kaki kuda. Dari
ujung arah barat di sebelah luar kastil datang
iring-iringan kecil perempuan yang me-
nunggang kuda. Mereka adalah istri dan
putri para tetua yang menunggu di belakang
Hiroshi. Mereka bersenjatakan ala perem-
puan wilayah Barat, menyandang busur di
bahu serta tabung berisi anak panah di
punggung mereka. Takeo mengagumi kuda-
kuda Maruyama yang tinggi dan gagah, dan
hatinya makin meluap-luap saat melihat
putrinya berada di punggung kuda yang
paling bagus, di tengah iringan itukuda
hitam yang dijinakkannya sendiri, dan diberi
nama Tenba.
Kuda itu terlalu bersemangat dan ber-
jingkrak, mengi-baskan kepala dan agak
mundur selagi Shigeko menyuruhnya ber-
henti. Shigeko duduk tenang bak patung;
rambutnya, dikuncir ke belakang, sama
hitamnya dengan surai dan ekor kuda yang
dia tunggangi, juga berkilauan seperti
kulitnya yang tertimpa sinar matahari musim
gugur. Tenba tenang dan santai.
Para perempuan di atas kuda menghadap
ke arah para laki-laki yang berdiri, dan tepat
di saat bersamaan, para tetua berlutut sambil
memegang kotak dengan merentangkan
tangan dan membungkuk dalam-dalam.
Hiroshi bicara dengan lantang. "Lady
Maruyama Shigeko, putri Shirakawa Kaede
dan sepupu kedua Maruyama Naomi, kami
menyambut Anda ke wilayah yang telah
dipertahankan atas kepercayaan bagi Anda."
Hiroshi melepaskan kakinya dari pijakan
sadel lalu turun dari kuda, menarik pedang
dari sabuknya lalu berlutut di hadapan
Shigeko, menyerahkan pedang dengan kedua
tangannya.
Sesaat Tenba terkejut karena gerakan
Hiroshi yang mendadak, dan Takeo melihat
penguasaan diri Hiroshi langsung buyar.
Disadarinya ternyata sikap Hiroshi lebih dari
sikap seorang ksatria pada atasannya.
Teringat olehnya minggu-minggu yang
mereka habiskan bersama untuk menjinak-
kan Tenba. Kecurigaannya terbukti sudah. Ia
tak tahu bagaimana perasaan putrinya, tapi
perasaan Hiroshi tak diragukan lagi. Kini
sudah jelas baginya, dan ia merasa heran
tidak menyadari hal itu sebelumnya. Perasaan
Takeo kesal sekaligus ibamustahil
memberikan keinginan Hiroshitapi ia
mengagumi pengendalian diri dan peng-
abdian pemuda itu. Itu karena mereka
dibesarkan bersama, pikirnya. Shigeko
menyayanginya, tapi hatinya tak tersentuh.
Dicermati putrinya baik-baik sewaktu dua
perempuan berkuda turun dari kuda lalu
memegangi tali kekang Tenba. Shigeko
meluncur turun dengan anggun dari
punggung kuda lalu menghadap ke Hiroshi.
Ketika Hiroshi menengadah, tatapan mereka
bertemu. Shigeko tersenyum tipis lalu
mengambil pedang itu. Kemudian ia berbalik
dan mengacungkan pedang itu tinggi-tinggi
ke setiap arah bergantian, membungkuk
hormat ke arah kerumunan orang, kepada
semua tetua dan rakyatnya.
Teriakan rakyat bergemuruh, seolah semua
yang hadir bicara dalam satu suara, lalu
suaranya pecan, bak gelombang menghempas
batu karang, menjadi sorak-sorai gegap
gempita. Kuda-kuda berjingkrak penuh
semangat. Shigeko menghunjamkan pedang
ke sabuknya lalu naik ke kudanya kembali,
begitu pula halnya dengan para perempuan
yang lain. Kuda-kuda berderap mengitari
dinding sebelah luar kastil, kemudian ber-
baris dalam satu barisan lurus ke arah
pinggiran, menuju sasaran. Tiap penunggang
kuda menjatuhkan tali kekang di leher kuda,
mengambil busur, menempatkan anak panah
lalu menariknya, semuanya dalam satu
gerakan cepat dan luwes. Anak-anak panah
beterbangan satu menyusul yang lainnya,
mengenai sasaran berbarengan. Akhirnya
Shigeko mendekat, kuda hitamnya berlari
laksana angin, laksana kuda dari surga, dan
anak panahnya tepat mengenai sasaran.
Shigeko membalikkan kuda lalu berderap
kembali, menarik tali kekangnya agar
berhenti di depan Takeo. Dia melompat dari
punggung Tenba lalu berkata dengan
lantang, "Maruyama bersumpah untuk ber-
sekutu dan setia pada Klan Otori, dan
sebagai pengakuannya saya persembahkan
kuda ini kepada Lord Otori, ayahku."
Dipegangnya tali kekang, lalu menunduk.
Sekali lagi terdengar seruan dari ke-
rumunan saat Takeo berdiri dan melangkah
turun dari mimbar. Menghampiri Shigeko
lalu mengambil tali kekang kuda itu dengan
begitu terharu sehingga tak mampu berkata-
kata. Tenba menurunkan kepala lalu
menggesek-gesekkan kepalanya ke bahu
Takeo. Kuda itu jelas keturunan kuda
Shigeru, Kyu dan Aoi, yang pernah terluka
parah oleh raksasa Jin-emon. Takeo
menyadari kalau bayangan masa lalu kini
mengelilingi dirinya: arwah mereka yang
telah berpulang, tatapan setuju mereka. Ia
merasa bangga dan bersyukur telah
membesarkan anak yang cantik ini, kalau
putrinya ini telah dewasa dan mendapaikan
warisannya.
"Kuharap Tenba bisa menjadi kuda
kesayangan Ayah seperti halnya Shun," ujar
Shigeko.
"Aku belum pernah melihat kuda yang
lebih hebatyang bergerak seperti terbang."
Takeo ingin sekali menunggangi kuda itu,
memulai ikatan panjang misterius
antarmakhluk hidup. Dia akan hidup Ubih
lama dariku, pikirnya dengan gembira.
"Maukah Ayah menungganginya?"
"Pakaian Ayah ini kurang cocok bila ber-
kuda," sahut Takeo. "Biar Ayah menun-
tunnya, dan kita akan berkuda bersama
nanti. Sementara itu, Ayah sangat berterima
kasih. Ini hadiah yang terindah."
Menjelang akhir senja, ketika matahari
mulai tenggelam. mereka berkuda di jalur
melewati pesisir ke mulut sungai.
Rombongan itu tidak hanya terdiri dari
Takeo, Shigeko dan Hiroshimeskipun
ketiganya lebih suka begitutapi juga ada
Lord Kono, Zenko dan Hana. Zenko
menyatakan kalau ia merasa mual dengan
jamuan dan upacara, dan perlu berkuda
untuk menjernihkan pikiran. Hana ingin
membawa keluar burung-burung rajawali
miliknya, dan Kono mengaku ingin berbagi
kegemaran dengan Hana saat berburu meng-
gunakan burung rajawali yang terlatih. Rute
perjalanan mereka melewati desa gelan-
dangan yang dibangun Takeo bertahun-
tahun lalu, ketika Jo-An masih hidup. Para
gelandangan masih menjemur kulit hewan di
sini sehingga dijauhi penduduk, tapi mereka
dibiarkan hidup dengan damai. Kini anak-
anak dari para gelandangan yang pernah
membangun jembatan yang memungkinkan
Takeo melarikan diri dari kejaran pasukan
Otori, juga terlihat cukup makan, sehat
seperti orangtuanya.
Takeo, Hiroshi dan Shigeko berhenti
untuk menyalami kepala desa, sementara
yang lainnya berjalan terus. Ketika mereka
menyusul kelompok berburu, rajawali yang
sudah dilepas terbang melayang di atas
padang rumput, bergerak kian kemari bak
ombak di laut, pancaran terakhir sinar
matahari berkilauan di sela-sela jambul di
kepalanya.
Takeo yang sudah bisa menyesuaikan diri
dengan kuda itu, membiarkannya melangkah
lebih bersemangat. Kuda ini mungkin tidak
sepandai Shun, tapi bersemangat dan sama
responsifnya, dan jauh lebih cepat. Satu kali
Tenba mundur ketika seekor ayam hutan
tertembak di bawah kakinya dengan gerakan
cepat dari sayapnya yang terbentang, dan
Takeo mesti mengerahkan tenaga untuk
mengingatkan siapa yang pegang kendali.
Beruntung aku tidak harus mengandalkannya
dalam pertempuran, katanya pada dirinya
sendiri. Masa-masa itu telah berakhir.
"Kau mengurusnya dengan baik," katanya
pada Shigeko.
"Meskipun Lord Otori memiliki
kekurangan, tapi itu tak mengurangi
kemahirannya berkuda," komentar Kono.
"Benar, aku lupa itu saat berkuda," kata
Takeo, tersenyum. Menunggang kuda
membuatnya merasa seperti muda kembali.
Merasa hampir menyukai Kono, kalau
ternyata dia telah salah menilai laki-laki itu,
dan kemudian marah pada dirinya sendiri
karena begitu mudah merasa tersanjung.
Di atas kepalanya keempat rajawali
terbang berputar-putar, dua di antaranya
menukik berbarengan dan tegak lurus ke
tanah. Salah satunya terbang tinggi lagi,
seekor ayam hutan dalam cengkeraman
cakarnya menggelepar: yang lainnya
memekik marah. Mengingatkan Takeo
bahwa yang kuat memangsa yang lemah,
begitu pula nantinya musuh-musuhnya
memangsanya. Dibayangkannya mereka
seperti rajawali, terbang melayang,
menunggu.
Mereka kembali saat matahari tenggelam,
bulan purnama muncul di balik pepohonan
plum, bentuk tubuh kelinci terlihat jelas di
bulatan yang berkilat. Jalan-jalan dipenuhi
kerumunan orang, biara dan toko kebanjiran
pengunjung, udara penuh aroma kue mochi
yang dipang-gang, ikan dan belut panggang,
minyak wijen dan kecap. Takeo bersyukur
dengan reaksi rakyatnya. Penduduk kota
memberi jalan dengan penuh hormat,
banyak di antaranya yang berlutut atau
menyeru namanya atau nama Shigeko.
Mereka tidak menatap dengan ketakutan,
atau pandangan putus asa dan kelaparan
seperti yang dialami Shigeru. Mereka tak lagi
butuh pahlawan menolong mereka. Mereka
melihat kesejahteraan dan kedamaian mereka
sebagai jalan hidup yang benar, diraih
dengan kerja keras dan kepandaian mereka
sendiri.*
Kastil dan kota sudah sunyi senyap. Bulan
sudah meninggi; langit malam penuh
bintang berkilauan. Takeo duduk bersama
Minoru, dua lentera menyala di dekat
mereka, meninjau kembali percakapan tadi
sore dan kesan yang didapat pemuda itu.
"Aku ingin keluar sebentar," kata Takeo
saat mereka sudah selesai. "Aku harus me-
nemui Taku karena aku hanya punya waktu
dua hari ini bila ingin mengantar Kono ke
Hofu sebelum musim dingin. Tetap di sini,
dan jika ada yang tanya, berpura-puralah kita
sedang mengurus bisnis penting jadi tak
ingin diganggu. Aku akan kembali sebelum
pagi."
Minoru sudah terbiasa dengan pengaturan
seperti ini dan dia hanya membungkuk.
Dibantunya Takeo berganti pakaian ber-
warna gelap yang sering dipakainya di malam
hari. Takeo melilitkan sehelai syal di kepala
untuk menutup wajah, dua botol sake,
pedang pendek dan sarung pisau lempar, lalu
disembunyikan di balik pakaiannya.
Andai Kono bisa melihatku sekarang,
pikirnya selagi melewati kamar bangsawan
itu. Takeo tahu kalau tak seorang pun bisa
melihatnya karena ia sedang menghilangkan
diri.
Bila menunggang kuda membuatnya
merasa kembali muda, begitu pula dengan
yang satu inikenikmatan mendalam yang
timbul oleh kemampuan kuno ini tak pernah
hilang, Setelah yakin tidak ada orang di
ujung caman, ia melompat ke puncak
dinding antara taman dan dinding sebelah
luar yang pertama. Berlari melintasi puncak
dinding ke seberang lalu menjatuhkan diri ke
atas lapangan kuda di dalam dinding sebelah
luar yang kedua. Umbul-umbul masih meng-
gelantung di sana, terkulai di bawah cahaya
bintang. Karena berpikir saat itu terlalu
dingin untuk berenang, maka setelah
menyeberang sungai ia memanjat merayap
dinding dan menyusuri sampai ke gerbang
utama. Para penjaga masih terjaga: ia men-
dengar para penjaga bicara saat ia melintasi
atap yang lebar dan melengkung, tapi mereka
tidak mendengarnya. Ia berlari melewati
jembatan, membiarkan dirinya terlihat
setelah sampai di ujungnya lalu berjalan
cepat-cepat ke kota yang penuh dengan jalan
dan lorong yang berliku-liku.
Ia tahu di mana Taku berada: kediaman
lama Muto. Dulu ia mengenai setiap rumah
Tribe di Maruyama, letak, ukuran dan
penghuninya. Ia masih menyesali cara yang
pernah ia gunakan saat pertama kali ke
Maruyama bersama Kaede; bertekad
menunjukkan kekejamannya pada Tribe:
membunuh atau mengeksekusi sebagian
besar dari mereka. Ia mengira satu-satunya
cara menghadapi kejahatan yaitu dengan
dibasmi, tapi kini, bila bisa mengulang masa
itu ia akan berusaha berunding tanpa
pertumpahn darah... Ia masih harus meng-
hadapi dilema itu: bila saat itu ia mem-
perlihatkan kelemahannya, maka ia takkan
sekuat sekarang untuk dapat memaksakan
kehendaknya dengan welas asih. Tribe
mungkin membencinya karena itu, tapi
setidaknya mereka tidak meremehkannya. Ia
sudah menyediakan cukup waktu untuk
membuat negerinya aman.
Di biara di ujung jalan, ia berhenti seperti
yang selalu dilakukannya, dan menaruh botol
sake di depan dewa keluarga Muto, me-
mohon maaf dari para mendiang.
Muto Kenji memaafkanku, katanya, dan
aku pun memaafkannya. Kami adalah teman
dekat dan sekutu. Semoga kalian mau
melakukan hal yang sama padaku.
Tidak ada yang memecahkan kesunyian
malam itu, tapi ia merasa tidak sendirian.
Takeo merangsek kembali ke dalam
bayangan, tangan di gagang pedang. Ia men-
dengar gemerisik di dedaunan yang telah
jatuh, seolah ada makhluk yang bergerak
melintasinya. Diintipnya ke arah suara tadi,
dan melihat dedaunan terserak pelan di
bawah pijakan kaki yang tak terlihat.
Ditangkupkan kedua tangan di depan dahi
untuk membuka mata lebih lebar, dan
kemudian melihat ke arah kirinya, men-
deteksi kemampuan menghilang. Makhluk
itu menatapnya dengan mata hijau berkilau
terkena sinar bintang.
Hanya seekor kucing, pikirnya, tipuan
cahayakemudian ia menyadari dengan
terperanjat ternyata tatapan mata kucing itu
mengunci tatapannya; ia merasa terkejut
karena ketakutan yang amat dalam. Kucing
itu seperti makhluk halus yang tinggal di
tempat ini, dikirim mereka yang sudah mati
untuk menghukumnya. Takeo merasa
hampir jatuh ke dalam sihir tidur Kikuta,
merasa kalau pembunuh Kikuta sedang
memanfaatkan makhluk halus ini. Segera
mempertahankan diri kini sudah menjadi
sifat keduanya, membunuh sebelum di-
bunuh. Memanggil semua kekuatan dalam
dirinya untuk mematahkan tatapan me-
matikan itu, lalu merogoh pisau lemparnya
dengan sembarangan. Begitu pisau pertama
yang terpegang langsung dilemparnya, me-
lihat pantulan cahaya bintang selagi pisau itu
berputar, mendengar akibatnya dan jerit
kesakitan hewan itu. Kemampuan meng-
hilang kucing itu sirna di saat melompat ke
arahnya.
Kini pedang sudah di tangannya. Dilihat-
nya kucing itu menunjukkan sederetan gigi.
Mahkluk itu memang kucing, tapi kucing
dengan ukuran dan kekuatan serigala.
Serangkaian cakarnya menggaruk wajah
Takeo saat ia berkelit lalu berbalik agar
cukup dekat untuk bisa menikam leher
kucing itu, lalu ia menampakkan diri agar
bisa lebih fokus pada serangannya.
Tapi kucing itu berkelit melarikan diri.
Jeritan kucing itu terdengar seperti jeritan
manusia. Di sela-sela rasa kaget dan takut
karena pertarungan itu, Takeo mendengar
suara yang sudah dikenalnya.
"Ayah," jerit hewan itu lagi. "Jangan sakiti
aku! Ini aku, Maya!"
Maya berdiri di hadapannya. Takeo mem-
butuhkan seluruh kekuatannya untuk dapat
menghentikan tikaman pisau yang nyaris
menggorok leher putrinya sendiri. Ia men-
dengar juga jerit putus asanya sendiri selagi
memaksa tangannya membelokkan arah
pisaunya. Pisau itu terjatuh dari
genggamannya. Meraih tubuh Maya lalu
menyentuh wajahnya, merasakan basah
karena darah atau air mata atau keduanya,
"Aku nyaris membunuhmu," kata Takeo
iba karena putrinya hampir terbunuh, sadar
dengan air mata di pelupuk matanya sendiri,
dan ketika menyingsingkan lengan baju
untuk menyekanya, dirasakannya sengatan
bekas dicakar, tetesan darah di wajahnya.
"Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau
di luar sendirian?" Hampir lega rasanya
mengungkapkan kebingungannya dengan
kemarahan.
"Maaf, aku menyesal," Maya menangis
seperti anak kecil, bingung dan sedih.
Dipeluknya Maya erat-erat, terkejut ternyata
putrinya sudah besar. Kepala Maya me-
nyembul di antara tulang dada Takeo;
badannya tegak dan keras, lebih mirip badan
anak laki-laki.
"Jangan menangis," ujar Takeo dengan
ketenangan penuh pengertian. "Kita akan
menemui Taku, dan dia akan menceritakan
pada Ayah apa yang terjadi pada dirimu."
"Aku menyesal telah menangis," katanya
dengan sesunggukan.
"Ayah kira kau menyesal karena sudah
berusaha membunuh ayahmu sendiri," sahut
Takeo seraya menggandeng tangan putrinya
melewati gerbang kuil ke jalanan.
"Tadi aku tidak tahu kalau itu Ayah. Aku
tidak bisa melihat Ayah. Kukira Ayah adalah
pembunuh Kikuta. Begitu mengenali Ayah,
aku berubah wujud. Aku tidak selalu
melakukan itu dengan cepat, tapi aku makin
pandai. Kendati aku tidak perlu menangis.
Aku tak pernah menangis. Lalu tadi kenapa
aku menangis?"
"Mungkin karena kau senang berjumpa
Ayah?"
"Memang," Maya meyakinkan. "Tapi aku
belum pernah menangis bahagia. Itu pasti
karena terkejut. Aku takkan menangis lagi."
"Tidak ada salahnya menangis," tutur
Takeo. "Tadi Ayah juga menangis."
"Kenapa? Apakah aku menyakiti Ayah?
Pasti tidak ada apa-apanya dibandingkan
dengan luka-luka yang pernah Ayah derita."
Maya menyentuh wajahnya sendiri, "Ayah
melukaiku lebih parah."
"Dan Ayah amat menyesal. Ayah lebih
baik mati daripada menyakitimu."
Dia sudah berubah, pikir Takeo; bahkan
cara bicaranya kasar, tanpa perasaan. Dan ada
semacam tuduhan yang kuat di balik kata-
katanya, sesuatu yang lebih dari sekadar luka
fisik. Ketidakpuasan apa lagi yang ada dalam
diri putrinya pada dirinya? Apakah kebencian
karena dikirim jauh dari rumah, atau sesuatu
yang lain?
"Kau seharusnya tidak di luar sendirian."
"Ini bukan salah Taku," sahut Maya cepat.
"Ayah jangan menyalahkannya."
"Siapa lagi yang harus disalahkan? Ayah
memercayakan dirimu padanya. Dan di
mana Sada? Ayah lihat kalian bertiga bersama
tadi pagi. Mengapa dia tak bersamamu?"
"Bukankah itu indah?" sahut Maya,
menghindari pertanyaannya. "Shigeko
kelihatan sangat cantik. Dan kuda itu! Ayah
suka dengan hadiahnya? Apakah Ayah ter-
kejut?"
"Entah mereka yang lengah atau kau yang
tak patuh," kata Takeo, menampik per-
hariannya dialihkan oleh komentar tiba-tiba
Maya yang kekanak-kanakan.
"Aku yang tidak patuh. Tapi aku memang
harus bersikap begitu karena aku bisa
melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan
orang lain. Tak ada orang yang bisa meng-
ajariku. Aku yang harus mencari tahu." Maya
menatap Takeo dengan tajam. "Kurasa Ayah
belum pernah melakukannya?"
Sekali lagi Takeo merasakan tantangan
yang lebih berat. Tak bisa disangkalnya, tapi
memutuskan untuk tak menjawab, apalagi
sekarangkarena mereka sudah dekat
gerbang kediaman Muto. Pedih terasa
menyengai wajahnya, dan tubuhnya terasa
sakit karena pertarungan yang tiba-tiba dan
keras tadi. Ia tak bisa melihat luka Maya
dengan jelas, tapi bisa membayangkannya
luka itu harus segera diobati bila tidak ingin
berbekas.
"Apakah keluarga di sini bisa dipercaya?"
bisik Takeo.
"Aku belum menanyakannya pada diriku
sendiri!" sahut Maya. "Mereka keluarga
Muto, kerabat Taku dan Sada. Pastinya
begitu, kan?"
"Baiklah, segera saja kita cari tahu,"
gumam Takeo, dan mengetuk gerbang yang
dipalang, memanggil-manggil penjaga di
dalam. Anjing menyalak marah.
Perlu waktu agar dapat meyakinkan
mereka untuk membuka gerbang karena
tidak segera mengenali Takeo, tapi mereka
mengenal Maya. Mereka melihat darah di
bawah sinar lentera yang mereka bawa,
berseru kaget lalu memanggil TakuTakeo
perhatikan, tidak satu pun dari mereka
menyentuh Maya. Tentu saja mereka meng-
hindari berdekatan dengannya, maka Maya
berdiri seolah dikeliligi pagar yang tak
nampak.
"Dan Anda, tuan, apakah Anda terluka
juga?" Salah satu orang menaikkan lentera
hingga sinarnya jatuh menimpa pipi Takeo
yang tak berusaha untuk menutupi dirinya;
ingin melihat reaksi mereka.
"Ini Lord Otori!" bisik laki-laki itu, dan
yang lainnya langsung berlutut. "Masuklah,
tuan." Laki-laki yang memegang lentera tadi
berdiri di samping, menerangi teras.
"Bangunlah," kata Takeo kepada orang-
orang yang berlutut. "Bawakan air, dan
sedikit kertas halus atau gumpalan kain sutra
untuk menghentikan pendarahannya." Takeo
melangkah melewati teras, dan gerbang di-
tutup dengan cepat lalu dipalang.
Penghuni rumah sudah terbangun; lentera
di dalam rumah dinyalakan, dan pelayan
berdatangan dengan mata masih mengantuk.
Taku muncul dari ujung beranda, berpakaian
jubah tidur berbahan katun, jaket berlapis
meng-gantung di bahunya. Dia melihat
Maya lebih dulu, dan langsung segera
menghampiri. Takeo kira Maya akan di-
pukultapi Taku memberi isyarat kepada
penjaga untuk membawakan lentera, lalu
memegangi kepala Maya dengan kedua
tangan lalu memiringkannya ke kanan dan ke
kiri agar bisa melihat luka di pipinya.
"Apa yang terjadi?" tanyanya.
"Kecelakaan," sahut Maya. "Aku meng-
halangi jalan."
Taku membimbing Maya ke beranda,
menyuruhnya duduk lalu berlutut di
sampingnya, mengambil segumpal kain dari
pelayan lalu merendamnya dalam air. Di-
basuhnya luka Maya dengan hati-hati,
meminta agar lentera lebih didekatkan.
"Ini kelihaian seperti terkena pisau lempar.
Siapa yang ada di luar sana dengan pisau
lempar?"
"Tuan, Lord Otori ada di sini," kata
penjaga. "Beliau juga terluka."
"Lord Takeo?" Taku memicingkan mala
ke arah Takeo. "Maaf tadi aku tak melihat.
Anda tak terluka parah, kan?"
'Tidak apa-apa," sahut Takeo, bergerak
menghampiri beranda. Di anak tangga, salah
satu pelayan maju untuk melepas sandalnya.
Takeo berlutut di samping Maya. "Mungkin
sulit untuk menjelaskan bagaimana aku bisa
melakukannya. Bekas lukanya akan kelihatan
selama beberapa waktu."
"Maafkan aku," Taku mulai angkat bicara,
tapi Takeo menaikkan tangan memberi
isyarat agar Taku diam.
"Kita bicara lagi nanti. Lakukan yang
terbaik untuk mengobati luka putriku. Aku
cemas lukanya akan berbekas."
"Panggilkan Sada." perintah Taku kepada
salah satu pelayan, dan beberapa waktu
kemudian perempuan muda itu muncul dari
ujung beranda, berpakaian seperti Taku
dengan jubah tidur, rambutnya yang
sepanjang bahu tergerai di wajahnya. Dia
melihat Maya secepatnya lalu masuk ke
rumah, kembali dengan membawa kotak
kecil.
"Ini salep pemberian Ishida," kata Taku,
seraya mengambil dan membukanya. "Pisau-
nya tidak beracun, kan?"
Tidak," sahut Takeo.
"Untung tidak terkena mata. Kau yang
melemparnya?"
"Kurasa begitu."
"Setidaknya kita tak harus mencari para
pembunuh Kikuta." Sada memegangi kepala
Maya sementara Taku mengoleskan salep itu
di lukanya; salep itu tampak agak lengket,
seperti lem, dan menyatukan pinggiran luka
sa-yatan. Maya duduk diam tanpa bergerak
kesakitan, bibirnya mengkerut seolah ingin
tersenyum, matanya terbuka lebar. Ada
semacam ikatan aneh di antara mereka bertiga,
pikir Takeo, karena adegan yang ada di
depannya ini sarat dengan muatan emosi.
"Ikut dengan Sada," kata Taku pada
Maya. "Berikan sesuatu untuk membuatnya
tidur," katanya pada Sada. "Dan temani dia
malam ini. Aku ingin bicara dengannya
besok pagi."
"Aku benar-benar menyesal," kata Maya.
"Aku tidak bermaksud menyakiti ayahku."
Namun nada suaranya justru kedengaran
bertentangan dengan perkataannya.
"Kami akan pikirkan hukuman yang akan
membuatmu lebih menyesal lagi," ujar Taku.
"Aku sangat marah, dan aku yakin Lord
Otori juga begitu."
"Mendekatlah," katanya pada Takeo. "Biar
kulihat apa yang telah dilakukannya pada-
mu."
"Mari masuk ke dalam," sahut Takeo.
"Lebih baik kita bicara berdua saja."
Sambil menyuruh pelayan membawakan
air segar dan teh, Taku berjalan di depan ke
ruang kecil di ujung beranda. Dilipatnya
tikar tidur lalu mendorongnya ke sudut. Satu
lentera masih menyala, dan di sebelahnya
berdiri sebotol sake dan mangkuk minum.
Takeo mengamati semua yang di ada di
ruangan itu tanpa sepatah kata pun.
"Semula aku berharap bertemu denganmu
sebelum kejadian ini," ujar Takeo, nada
suaranya terdengar dingin. "Aku tak berharap
berjumpa putriku dengan cara seperti ini."
"Benar-benar tak ada alasan," sahut Taku.
"Tapi aku obati dulu luka Anda; duduk di
sini, dan minum ini." Taku menuang sake
terakhir ke mangkuk dan memberikannya
kepada Takeo.
"Kau tidak tidur sendirian, tapi kau
minum sendirian?" Takeo menghabiskan
sake dengan sekali leguk.
"Sada tidak menyukainya." Dua laki-laki
muncul di pintu, yang satu membawa air,
dan yang satunya lagi membawa teh. Taku
mengambil mangkuk berisi air lalu
membasuh pipi Takeo, Bekas cakarannya
terasa perih.
"Bawakan sake lagi untuk Lord Otori,"
pinta Taku pada si pelayan. "Darahnya
cukup banyak," gumamnya. "Cakarnya
menyayat cukup dalam."
Taku terdiam ketika si pelayan kembali
dengan membawa sebotol sake. Lalu pelayan
itu mengisi mangkuk minum sampai penuh
lalu Takeo menenggaknya sampai habis lagi.
"Kau punya cermin?" tanya Takeo pada
pelayan itu.
Dia mengangguk. "Akan kuambilkan."
Si pelayan kembali dengan membawa
sebuah benda yang lerbungkus kain coklat
tua, berlutut lalu menyerahkannya pada
Takeo. Dibukanya bungkusan itu. Cermin
itu sangat berbeda dengan yang pernah
dilihatnya, pegangannya panjang, bulat,
permukaan kacanya mengkilap. Takeo jarang
melihat bayangannya sendiridan belum
melihat dengan begitu jelasdan kini takjub
pada wajahnya sendiri. Ia tidak pernah tahu
bagaimana wajahnyasangat mirip Shigeru,
namun lebih kurus dan lebih tua. Bekas
cakaran di pipinya memang dalam, pinggiran
luka merah hati, darah yang mengering
berwarna lebih gelap.
"Cermin ini berasal dari mana?"
Pelayan itu menatap Taku dan bergumam,
"Dari Kumamoto. Sesekali pedagang mem-
bawa barang dagangan, seorang laki-laki
Kuroda, Yasu. Kami membeli pisau dan
peralatan darinyadia juga membawa
cermin ini."
"Kau pernah lihat cermin ini?" tanya
Tiikeo pada Taku.
"Belum untuk yang satu ini. Aku pernah
lihat cermin yang serupa di Hofu dan Akashi.
Cermin-cermin ini cukup populer." Diketuk
bagian permukaannya. "Terbuat dari kaca."
Bagian belakangnya terbuat dari semacam
logam yang tidak segera dikenali oleh Takeo,
diukir atau dibentuk menjadi motif bunga-
bunga yang saling terjalin.
"Benda ini dibuat di negeri seberang,"
tuturnya.
"Sepertinya begitu," Taku setuju.
Takeo melihat lagi bayangan wajahnya.
Sesuatu tentang cermin asing itu meng-
ganggunya. Dan ia berusaha menyingkirkan
perasaan itu sekarang.
"Bekas luka ini akan lama hilangnya,"
katanya.
"Uhh," Taku setuju, seraya menyeka luka
itu dengan segumpal kertas bersih untuk
mengeringkannya; lalu dia mulai mengoles-
kan salep yang lengket itu.
Takeo mengembalikan cermin itu kepada
si pelayan. Ketika perempuan itu pergi, Taku
berkata, "Seperti apa wujudnya?"
"Kucing itu? Ukurannya sebesar serigala,
dan memiliki tatapan maut Kikuta. Kau
belum pernah melihainya?"
"Aku pernah merasakan kucing itu ada
dalam diri Maya, dan beberapa malam lalu
Sada dan aku sempat melihatnya sekilas.
Kucing itu bisa menembus dinding.
Kekuatannya luar biasa besar. Maya menolak
kehadirannya saat aku ada, kendati aku
sudah berusaha membujuknya agar
membiarkan sosok kucing itu keluar. Maya
harus belajar mengendalikannya: saat ini
sepertinya roh kucing itu mengambil alih
saat pertahanan diri Maya lemah."
"Dan ketika dia sendirian?"
"Kami tak bisa mengawasinya setiap
waktu. Dia harus patuh; harus bertanggung
jawab atas perbuatannya."
Takeo merasakan amarahnya meluap.
"Aku tak mengharapkan dua orang yang
kupercayakan putriku akan berakhir dengan
tidur bersama!"
"Aku pun tidak mengharapkannya," sahut
Taku pelan. "Tapi itu sudah terjadi. dan
akan berlanjut."
"Mungkin kau harus kembali ke Inuyama,
dan kepada istrimu!"
"Istriku tahu kalau aku selalu punya
perempuan lain, di Inuyama dan dalam
perjalanan-perjalananku. Tapi Sada berbeda.
Sepertinya aku tidak bisa hidup tanpa dia."
"Kebodohan macam apa ini? Jangan
katakan kalau kau sedang dimabuk cinta!"
"Mungkin benar. Bisa kukatakan kalau
kemanapun aku pergi, dia akan ikut
denganku, bahkan ke Inuyama."
Takeo tercengang karena Taku begitu
dimabuk cinta dan dia tidak berusaha
menyembunyikannya.
"Kurasa ini menjelaskan alasan kau pergi
jauh dari kastil."
"Hanya sebagian. Sebelum kejadian
dengan si kucing, setiap hari aku bersama
Hiroshi dan Lord Kono. Tapi Maya merasa
amat tertekan dan aku tak ingin mening-
galkannya. Jika kuajak dia bersamaku. Hana
pasti akan mengenalinya, bertanya-tanya
tentang Maya. Semakin sedikit orang yang
tahu tentang masalah kerasukan ini. lebih
baik. Ini bukan jenis laporan yang mesti
dibawa Kono kembali ke ibukota. Aku
tengah memikirkan rencana Anda menikah-
kan putri sulung Anda. Aku tidak ingin
memberikan Hana dan Zenko senjata lebih
banyak lagi untuk mereka gunakan melawan
Anda. Aku tidak memercayai keduanya. Aku
sempat berbincang dengan kakakku tentang
topik pembicaraan yang cukup mengganggu
yaitu kepemimpinan keluarga Muto. Dia
bertekad untuk memaksakan haknya sebagai
penerus Kenji, dan ada beberapaaku tak
tahu ada berapa banyakpihak yang tidak
senang dengan gagasan perempuan berkuasa
atas diri mereka."
Jadi naluri Takeo benar untuk tidak
memercayai keluarga Muto.
"Apakah mereka mau menerimamu?"
tanya Takeo.
Takeo menuang sake lagi untuk mereka
berdua, lalu meminumnya. "Aku tak ingin
menyinggung Anda, Lord Otori, tapi hal-hal
semacam ini selalu diputuskan dalam lingkup
keluarga, bukan dengan orang luar."
Takeo mengambil cangkirnya lalu minum
tanpa bicara. Akhirnya dia berkata, "Kau
membawa banyak berita huruk malam ini.
Apa lagi yang mesti kau katakan padaku?"
"Akio berada di Hofu, dan sejauh yang
bisa kami tahu, dia berencana menghabiskan
musim dingin di wilayah Barataku takut
kalau dia akan pergi ke Kumamoto."
"Bersamaanak itu?"
"Sepertinya begitu." Tak satu pun dari
mereka bicara selama beberapa saat.
Kemudian Taku berkata, "Akan cukup
mudah untuk menyingkirkan mereka di
Hofu, atau dalam perjalanan. Biar aku yang
mengaturnya. Begitu Akio sampai di
Kumamoto, jika dia menghubungi kakakku
maka dia akan disambut di sana, bahkan
ditampung."
"Tak boleh ada orang yang menyentuh
anak itu."
"Baiklah, hanya Anda yang bisa memutus-
kan itu. Satu lagi yang kutahu adalah
Gosaburo sudah mati. Dia ingin berunding
dengan Anda demi nyawa anak-anaknya,
olah karena itulah Akio membunuhnya."
Berita ini, dan juga sikap Taku yang terus
terang, amat mengejutkannya. Gosaburo
pernah memerintahkan hukuman mati
untuk banyak orangsalah satunya, setidak-
nya, pernah dilaksanakan Takeo sendiri
tapi ternyata Akio malah berbalik mem-
bunuh pamannya, sama seperti saran Taku
kalau ia sendiri yang harus membunuh putra-
nya sendiri, memaksa dirinya mengingat
kekejaman tanpa ampun Tribe. Melalui
Kenji, dia berhasil mengendalikannya, tapi
kini kendalinya atas diri mereka sedang diuji.
Mereka selalu menyatakan bahwa bangsawan
bisa berkuasa dan jatuh, tapi Tribe akan
selamanya ada. Tapi bagaimana ia meng-
hadapi musuh yang tak mudah ditangani ini,
yang tak mau berunding dengannya?
"Anda harus memutuskan nasib sandera di
Inuyama," ujar Taku. "Anda mesti meng-
eksekusi mereka sesegera mungkin. Bila tidak
Tribe akan menganggap Anda lemah, dan itu
akan menimbulkan lebih banyak per-
selisihan."
"Aku akan bicarakan itu dengan istriku
saat sudah kembali ke Hagi nanti."
"Jangan terlalu lama," Taku mendesak.
Takeo bertanya pada dirinya sendiri
apakah Maya mesti pulang bersamanyatapi
cemas dengan ketenangan pikiran Kaede, dan
kesehatan istrinya selama kehamilannya.
"Bagaimana dengan Maya?"
"Dia bisa tinggal bersamaku. Aku tahu
Anda merasa kecewa, tapi terlepas dari
kejadian malam ini, kami sudah membuat
kemajuan. Dia belajar mengendalikan
kerasukan itudan siapa yang tahu manfaat
apa yang mungkin bisa kita ambil darinya.
Maya berusaha membuat Sada dan aku
senang: dia memercayai kami."
"Tapi yang pasti kau tidak berencana jauh
dari Inuyama selama musim dingin, lean?"
"Aku tidak boleh terlalu jauh dari wilayah
Barat. Aku harus terus mengawasi kakakku.
Mungkin aku akan menghabiskan musim
dingin di Hofu: cuacanya lebih lembut, dan
aku bisa mendengar semua desas-desus yang
datang dan pergi melalui pelabuhan."
"Dan Sada akan ikut denganmu?"
"Aku membutuhkan Sada, terutama bila
aku harus membawa Maya."
"Baiklah." Kehidupan pribadinya bukan-
lah urusanku, pikir Takeo. "Lord Kono juga
akan ke Hofu. Dia akan kembali ke ibukota."
"Dan Anda sendiri?"
"Kuharap bisa tiba di rumah sebelum
musim dingin. Aku akan tinggal di Hagi
sampai anak kami lahir. Lalu saat musim
semi aku harus pergi ke Miyako."
***
Takeo kembali ke kastil Maruyama tepat
sebelum matahari terbit, kelelahan dengan
kejadian malam itu, bertanya-tanya apa yang
sedang dilakukannya selagi mengumpulkan
lagi semua tenaganya yang melemah untuk
ecnghilang, merayap di dinding lalu kembali
ke kamarnya tanpa ketahuan. Perasaan
senangnya pada kemampuan Tribe sebelum-
nya telah sirna. Kini ia hanya merasa jijik
pada dunia yang gelap itu.
Aku sudah terlalu tua untuk ini, katanya
pada dirinya saat menggeser pintu terbuka
lalu melangkah masuk. Penguasa macam apa
yang mengendap-ngendap malam-malam
dengan cara seperti ini, bak pencoleng? Aku
pernah lolos dari cengkeraman Tribe, dan
kukira aku telah meninggalkannya untuk
selama-lamanya, tapi kekuatannya masih saja
menjerat diriku, dan warisan yang kuturunkan
pada putri-putriku bukan berarti aku akan
bebas.
Takeo merasa amat terganggu dengan
semua hal yang belum diketahuinya: lebih
dari semuanya, keadaan Maya. Wajahnya
meringis kesakitan; kepalanya pusing.
Kemudian teringat masalah dengan cermin
tadi. Itu menandakan kalau barang-barang
asing diperdagangkan di Kumamoto. Tapi
orang-orang asing itu seharusnya dikurung di
Hofu, dan kini di Hagi: adakah orang asing
lain di negeri ini? Jika mereka berada di
Kumamoto, Zenko pasti mengetahuinya,
namun dia tidak mengatakan sepatah kata
pun tentang hal inibegitu pula Taku.
Pikiran kalau Taku menyembunyikan
sesuatu memenuhi dirinya dengan ke-
marahan. Entah Taku menyembunyikannya
atau dia memang tidak tahu. Perselingkuhan-
nya dengan Sada juga membuatnya khawatir.
Laki-laki cenderung bersikap ceroboh saat
terjerat asmara. Bila aku tak bisa memercayai
Taku, tamatlah riwayatku. Tapi mereka kakak
beradik...
Kamar itu sudah terang saat Takeo
tertidur.
Ketika terbangun, diperintahkannya untuk
mengurus keberangkatannya, dan meng-
instruksikan Minoru untuk menulis surat
pada Arai Zenko, memintanya menunggu
Lord Otori.
Hari sudah sore ketika Zenko datang,
dibawa dengan tandu dan didampingi
sebarisan pengawal, semuanya berpakaian
mewah, cakar beruang Kumamoto tergambar
jelas di jubah dan panji-panjinya. Bahkan
dalam beberapa bulan sejak berjumpa di
Hofu, penampilan Zenko dan pendamping-
nya sudah berubah. Dia semakin mirip
ayahnya, secara fisik mengesankan dan
dengan kepercayaan diri yang makin tinggi:
tingkahnya, anak buah dan semua pakaian
sena senjata mereka berbicara dengan keme-
wahan dan mementingkan diri sendiri.
Takeo sendiri telah mandi dan berpakaian
dengan patut untuk pertemuan ini,
mengenakan jubah resminya yang tampak
menambah tinggi badannya dengan bentuk
bahu melebar dan kaku sena lengan panjang.
Tapi ia tidak bisa menyembunyikan luka di
pipinya, sayatan cakar, dan Zenko berseru
kaget saat melihatnya, "Apa yang terjadi?
Anda terluka? Tentunya tidak ada yang
menyerang Anda, kan? Aku tidak mendengar
beritanya'"
"Bukan apa-apa," sahut Takeo. "Aku jatuh
tersandung ranting di taman semalam." Dia
akan mengira aku mabuk, atau bersama
perempuan, pikirnya, dan akan makin mem-
benciku. Karena dilihatnya ekspresi wajah
Zenko yang merengut seperti tidak suka dan
benci.
Hari itu terasa dingin dan lembap, hujan
turun tadi pagi. Daun-daun merah pohon
maple berubah warna menjadi lebih gelap
dan mulai berguguran. Sesekali angin ber-
hembus di taman, membuat dedaunan
melayang dan menari-nari.
"Ketika kita bertemu di Hofu awal tahun
ini, aku berjanji membicarakan masalah
pengangkatan anak pada saat ini," tutur
Takeo. "Kau tentunya mengerti kalau ke-
hamilan istriku menyebabkan tindakan
formal apa pun sebaiknya ditunda."
"Tentu saja kami berharap Lady Otori
memberi Anda anak laki-laki," sahut Zenko.
"Pada dasarnya, putra-putraku takkan men-
dahului keturunan Anda."
"Aku menyadari kepercayaan yang kau
miliki pada keluargaku," kata Takeo. "Dan
aku berterima kasih yang sedalam-dalamnya
padamu. Aku menganggap Sunaomi dan
Chikara sebagai anakku sendiri...." Takeo
seperti melihat kekecewaan di wajah Zenko,
dan merasa, aku harus menawarkan sesuatu
kepadanya. Ia berhenti bicara selama
beberapa saat.
Takeo pernah berjanji untuk tidak men-
jodohkan putri-putrinya saat mereka masih
muda, namun ternyata ia berkata, "Aku
usulkan Sunaomi dan putri bungsuku, Miki,
ditunangkan saat mereka memasuki usia akil
balik kelak."
"Sungguh suatu kehormatan." Zenko
tidak terdengar gembira dengan usulan ini,
kendati semua kata-katanya terdengar patut.
"Aku akan bicarakan kebaikan yang tiada
tara ini dengan istriku saat kami menerima
dokumen res mi tentang tawaran ini: harta
benda apa yang akan mereka terima, di mana
mereka akan tinggal dan sebagainya."
"Tentu saja," sahut Takeo, seraya berpikir,
Dan aku harus membicarakannya dengan
istriku. "Mereka berdua masih sangat muda.
Masih ada banyak waktu." Setidaknya
tawaran sudah diajukan. Dia tidak bisa
menyatakan kalau aku telah menghinanya.
Tak lama kemudian Shigeko, Hiroshi, dan
Miyoshi bersaudara datang bergabung, dan
perbincangan beralih ke pertahanan wilayah
Barat, ancaman atau kekurangan yang
ditanyakan orang-orang asing, hasil dan
bahan-bahan yang orang-orang asing ingin
perjualbelikan. Takeo menyebutkan tentang
cermin, bertanya dengan santai apakah benda
semacam itu bisa dibeli di Kumamoto.
"Mungkin," sahut Zenko mengelak.
"Benda-benda itu masuk melalui Hofu,
kurasa. Perempuan sangat menyukai barang-
barang baru semacam itu! Kurasa istriku
pernah menerima beberapa sebagai hadiah."
"Jadi tidak ada orang asing di
Kumamoto?"
"Tentu saja tidak ada!"
Zenko membawa catatan dan laporan
tentang semua kegiatannya: senjata yang
sudah ditempanya, biji besi yang dibelinya;
segalanya tampak teratur, dan dia mengulang
keberatannya atas kesetiaaan kewajiban
feodal. Takeo tidak berbuat apa-apa selain
menerima kalau catatan itu benar, keberatan
tersebut memang apa adanya. Ia berbicara
singkat tentang usulan untuk mengunjungi
Kaisar, mengetahui kalau Kono pasti sudah
membicarakannya dengan Zenko; ditekan-
kan niatnya yang penuh damai, dan men-
ceritakan pada Zenko kalau Hiroshi maupun
Shigeko akan ikut mendampinginya.
"Bagaimana dengan Lord Miyoshi?" tanya
Zenko, menatap sekilas ke arah Kahei. "Dia
akan berada di mana tahun depan?"
"Kahei akan tinggal di Tiga Negara," sahut
Takeo.
"Tapi dia akan pindah ke Inuyama sampai
aku kembali dengan selamat. Gemba ikut
bersama kami ke Miyako."
Tak ada yang menyebutkan bahwa
sebagian besar kekuatan Negara Tengah akan
menunggu di perbatasan wilayah Timur di
bawah perintah Miyoshi Kahei, tapi tak
mungkin menutupi kabar ini dari Zenko.
Pikiran Takeo melayang pada bahaya
meninggalkan Negara Tengah tanpa per-
lindungantapi Yamagata dan Hagi hampir
tak mungkin diduduki, dan penduduknya
pasti akan melawan. Kaede pasti mem-
pertahankan Hagi melawan serangan dari
manapun, dan istri juga putra-putra Kahei
akan melakukan hal yang sama di Yamagata.
Mereka melanjutkan pembicaraan hingga
hampir larut malam, sementara sake dan
makanan disajikan. Selagi undur diri, Zenko
berkata kepada Takeo, "Ada satu hal lagi
yang harus kita bicarakan. Bisakah Anda
keluar ke beranda? Sebaiknya hal ini ku-
bicarakan berdua saja."
"Tentu," sahut Takeo setuju dengan
ramah. Hujan turun lagi; angin terasa
dinginTakeo merasa lelah, ingin sekali
tidur. Mereka berdiri di bawah naungan
tepian atap yang meneteskan air hujan.
Zenko berkata, "Ini soal keluarga Muto.
Kesan yang kudapat adalah banyak pihak di
keluargaku, di seluruh penjuru Tiga Negara.
sementara mereka amat menghormati ibuku
dan juga Anda, merasa kalaubagaimana
cara mengatakannya?tidak beruntung,
bahkan salah, dipimpin perempuan. Mereka
mempertimbangkan aku sebagai kerabat laki-
laki tertua dari Kenji untuk menjadi pewaris-
nya." Zenko melihat sekilas pada Takeo.
"Aku tak ingin menyinggung Anda, tapi
orang-orang tahu keberadaan cucu Kenji,
putra Yuki. Ada rumor yang mengatakan
kalau dialah yang seharusnya mewarisi
jabatan itu. Sebaiknya aku cepat-cepat di-
tunjuk sebagai pimpinan keluarga: ini bisa
membungkam rumor semacam itu dan
meyakinkan untuk menegakkan tradisi."
Senyum tipis kepuasan sesaat menari-nari di
wajahnya.
"Anak itu tentu saja merupakan pewaris
Kikuta," lanjutnya. "Lebih baik tetap
menjauhkannya dari Muto."
"Tidak ada yang tahu apakah dia masih
hidup atau sudah mati, ditambah lagi
keberadaannya," ujar Takeo, berpura-pura
bersikap ramah yang sebenarnya telah sirna
dari dalam dirinya.
"Oh, kurasa mereka tahu," bisik Zenko,
dan seraya memperhatikan reaksi kemarahan
Takeo, "Aku hanya berusaha membantu
Lord Otori dalam situasi yang sulit ini."
Andai kita bukan saudara ipar, Andai
ibunya bukan sepupuku dan salah satu
sahabatku, aku akan penntah dia mencabut
nyawanya sendiri! Aku harus melakukannya.
Aku tak bisa memercayainya. Aku hams me-
lakukannya sekarang juga, saat dia masih di
Maruyama dan dalam kekuasaanku.
Takeo diam sementara pikirannya ber-
kecamuk hebat. Akhirnya ia berkata,
berusaha bersikap halus, "Zenko, aku
sarankan kau tidak mendesakku lebih jauh
lagi. Kau memiliki tanah dan bangunan yang
luas, tiga putra, serta istri yang cantik. Aku
telah menawarimu persekutuan yang lebih
dalam dengan keluargaku melalui ikatan
pernikahan. Aku menghargai persahabatan
kita dan memandangmu dengan penuh
hormat. Tapi aku takkan membiarkanmu
menantangku...."
"Lord Otori!" protes Zenko.
"Atau menyebabkan perang saudara di
negara kita. Kau sudah bersumpah setia
kepadaku; kau berutang nyawa padaku.
Mengapa aku selalu harus mengulang-ulang-
nya? Aku lelah. Untuk yang terakhir kalinya,
kuanjurkan kau kembali ke Kumamoto dan
menikmati hidup yang kuberikan padamu.
Bila tidak, aku akan memintamu untuk
mengakhirinya."
"Anda tidak akan mempertimbangkan
pendapatku tentang pewarisan di keluarga
Muto?"
"Aku mendesakmu untuk mendukung
ibumu sebagai pimpinan keluarga dan
mematuhinya. Lagipula, kau sudah memilih
cara hidup sebagai ksatriaaku tidak
mengerti mengapa kau mencampuri masalah
Tribe!"
Saat ini Zenko gusar, dan kurang berhasil
menutupinya! "Aku dibesarkan oleh Tribe.
Aku juga anggota keluarga Muto seperti
halnya Taku."
"Hanya ketika kau melihat ada ke-
untungan politis di baliknya! Jangan pikir
kau bisa terus tidak terkendali untuk me-
nentang wewenangku. Jangan pernah lupa
kalau kedua putramu ada di tanganku
sebagai sandera atas kesetiaanmu."
Itu pertama kalinya Takeo secara langsung
mengancam anak-anak itu. Surga selamatkan
diriku karena aku harus membuat ancaman
ini, pikirnya. Tapi yang pasti Zenko takkan
mempertaruhkan nyawa kedua putranya.
"Aku mengusulkan ini agar seluruh negara
ini lebih kuat, dan untuk mendukung Lord
Otori," tutur Zenko. "Aku minta maaf
karena telah membicarakannya. Mohon
dilupakan saja."
Saat kembali, bagi Takeo, peran mereka
bak dalam pertunjukan drama, diarahkan
oleh tangan nasib untuk memainkan peran
mereka sampai habis; ruang penonton,
dihiasi dengan pahatan timbul emas di pilar
dan kasaunya, penuh dengan pengawal
berjubah warna-warna cemerlang menjadi
latarnya. Saling menyembunyikan ke-
marahan, mereka mengucapkan selamat
tinggal dengan sikap sopan yang dingin.
Keberangkatan Zenko dari Maruyama
direncanakan keesokan harinya, sementara
Takeo lusa.
"Jadi kau akan sendirian di wilayahmu
ini," kata Takeo kepada Shigeko sebelum
mereka beristirahat.
"Hiroshi akan berada di sini untuk mem-
bantuku, setidaknya sampai tahun depan,"
sahut Shigeko. "Tapi apa yang terjadi pada
Ayah tadi malam? Siapa yang membuat Ayah
terluka seperti itu?"
"Aku tidak bisa menyimpan rahasia
darimu," sahut Takeo. "Tapi aku tak ingin
menganggu ibumu di saat seperti ini, jadi
pastikan kalau ibumu tak mendengarnya,"
Takeo menceritakan dengan singkat tentang
Maya, tentang kerasukan dan hasilnya.
Shigeko mendengarkan tanpa bicara, tidak
menunjukkan ekspresi kaget maupun takut,
dan Takeo berterima kasih yang tak terkira
kepadanya.
"Maya akan berada di Hofu bersama Taku
selama musim dingin," ujar Takeo.
"Kemudian kita harus terus berhubungan
dengan mereka. Dan kita juga akan meng-
awasi Zenko dengan cermat. Ayah jangan
khawatir. Dalam Ajaran Houou kami sering
menghadapi masalah seperti kerasukan
hewan ini. Gemba tahu banyak tentang hal
ini, dan dia pernah mengajariku."
"Apakah Maya mesti ke Terayama?"
"Dia akan ke sana di waktu yang tepat."
Shigeko tersenyum lembut saat Takeo
melanjutkan bicara. "Semua roh mencari
kekuatan yang lebih besar yang bisa mengen-
dalikan mereka dan memberi kedamaian."
Takeo bergidik. Shigeko tampak seperti
orang asing, penuh teka-teki dan bijaksana,
Tiba-tiba ia teringat pada perempuan buta
yang mengatakan ramalannya, yang me-
nyebut nama kecilnya dan mengenal siapa
dirinya sebenarnya. Aku harus kembali ke
sana, pikirnya. Aku akan ziarah ke
pegunungan, tahun depan setelah anakku
lahir, setelah perjalananku ke ibukota.
Ia merasa kalau Shigeko memiliki
kemampuan spiritual yang sama. Semangat-
nya bangkit lagi selagi memeluk putrinya lalu
mengucapkan selamat malam.
"Kurasa Ayah harus menceritakannya pada
Ibu," kata Shigeko. "Seharusnya Ayah jangan
menyimpan rahasia dari Ibu. Ceritakan
tentang Maya. Ceritakan semuanya pada
Ibu."*
Kumamoto, kota kastil Arai, terbentang di
barat daya Tiga Negara, dikelilingi pe-
gunungan yang kaya akan bijih besi dan batu
bara. Sumber alam ini menyebabkan per-
kembangan industrinya maju pesat untuk
segala macam bentuk peralatan dari logam,
dan terutama pembuatan pedang. Banyak
perajin pedang serta tempat penempaan besi
yang sudah terkenal, begitu pula halnya
waktu belakangan ini, berkembang bisnis
yang bahkan lebih menguntungkan, yaitu
membuat senjata api.
"Paling tidak," gerutu si tua, Koji, "Akan
lebih menguntungkan jika Otori ijinkan kita
memproduksi hasil yang cukup untuk
memenuhi permintaan. Pompa yang keras,
nak."
Hisao memompa pegangan dengan tiupan
sekuat tenaga dan kotak pemanas semakin
panas, dengan hawa panas yang seakan
membakar wajah dan tangannya. Hisao tidak
keberatan karena musim dingin sudah tiba
sejak mereka sampai di Kumamoto dua
minggu lalu; angin dingin berhembus dari
laut keabuan, dan tiap malam terasa dingin
menggigit.
"Apa hak mereka mendikte Arai apa yang
boleh dibuat dan apa yang tidak boleh
dibuat, apa yang boleh kami jual dan apa
yang dilarang!" imbuh Koji.
Hisao mendengar nada tidak senang yang
sama di mana-mana. Ayahnya mengatakan,
dengan gembira, bahwa para pengawal Arai
tiada henti menghembuskan desas-desus,
membangkitkan ketidaksenangan untuk me-
nentang Otori, mempertanyakan mengapa
Kumamoto kini tunduk pada Hagi ketika
Arai Daiichi sudah menaklukkan seluruh
Tiga Negara, tak seperti Otori Takeo yang
hanya mengambil keuntungan dari gempa,
lalu menyebabkan kematian Lord Arai
dengan menggunakan senjata api yang sama
yang kini dilarangnya.
Akio dan Hisao mengetahui saat mereka
tiba di Kumamoto bahwa Zenko tidak ada di
sanadia dipanggil ke Maruyama oleh Lord
Otori.
"Memperlakukannya bak pelayan," ujar
penjaga penginapan pada malam pertama
mereka, saat makan malam. "Mengharapkan
Arai menyerahkan semuanya. Belum cukup-
kah Otori menyandera kedua putra Arai?"
"Dia suka mempermalukan sekutu mau-
pun musuhnya," ujar Akio. "Untuk memuas-
kan kesombongannya sendiri. Tapi sebenar-
nya dia tidak punya kekuatan. Dia akan
jatuh, dan Otori pun akan tumbang ber-
samanya."
"Akan ada perayaan di Kumamoto pada
hari itu," sahut laki-laki yang satu lagi,
sambil mengangkat semua piring lalu
kembali ke dapur.
"Kita tunggu sampai Arai kembali," kata
Akio pada Kazuo.
"Setelah itu kita akan membutuhkan
dana," ujar Kazuo. "Terutama dengan tiba-
nya musim dingin. Uang Jizaemon sudah
hampir habis."
Hisao tahu kalau hanya ada sedikit
keluarga Kikuta di wilayah ujung Barat, dan
mereka adalah keluarga yang kehilangan
kekuasaan dan pengaruh selama masa peme-
rintahan Otori. Kendati demikian, beberapa
hari kemudian, seorang pemuda berwajah
tajam datang meminta dipanggilkan Akio
pada satu malam. Dia memberi salam dengan
sikap tunduk dan gembira, dan memanggil
Akio dengan sebutan Ketua serta meng-
gunakan bahasa dan lambang rahasia
keluarga Kuroda. Pemuda itu bernama Yasu;
berasal dari Hofu dan lari ke Kumamoto
setelah bermasalah di sana karena terlibat
dalam penyelundupan senjata api.
"Aku sudah mati!" selorohnya. "Lord Arai
harus mengeksekusi diriku atas perintah Lord
Otori; tapi untungnya dia masih meng-
anggapku terlalu berharga, dan membuat
pertukaran."
"Apakah ada banyak orang sepertimu yang
bekerja pada Arai?"
"Ya, ada banyak. Keluarga Kuroda selalu
berhubungan dengan Muto, seperti yang kau
tahu, tapi kami juga punya banyak hubungan
dengan Kikuta. Lihatlah Shintaro yang hebat!
Separuh Kuroda, separuh Kikuta."
"Dibunuh Otori, seperti Kotaro," Akio
mengamati dengan tenang.
"Masih banyak kematian yang belum ter-
balaskan," ujar Yasu sepakat. "Keadaannya
berbeda saat Kenji masih hidup, tapi sejak
kematiannya, semenjak Shizuka menjadi
ketuasegalanya berubah. Tak ada yang
merasa senang. Pertama-tama karena merasa
tidak benar dipimpin seorang perempuan,
dan yang kedua karena Otori yang mengatur-
nya. Seharusnya Zenko yang menjadi
pimpinan, dialah kerabat laki-laki tertua dan
bila dia tak ingin meneruskannya, dengan
menjadi bangsawan besar, maka seharusnya
jabatan itu dipegang Taku."
"Taku adalah tangan kanan Otori, dan ter-
libat dalam kematian Kotaro," tutur Kazuo.
"Lagipula, saat itu dia masih kecil, dan
masih bisa dimaafkantapi tidak benar
kalau hubungan antara Muto dan Kikuta
menjadi begitu jauh. Dan itu juga ulah
Otori."
"Kami di sini untuk memperbaiki
jembatan yang terputus dan menyembuhkan
luka," tutur Akio kepadanya.
"Memang itulah yang kami harapkan.
Lord Zenko akan senang, bisa kukatakan itu
padamu."
Yasu membayar penjaga penginapan lalu
mengajak mereka ke tempat menginapnya
sendiri, di belakang toko tempat dia menjual
pisau dan peralatan dapur lainnya. Yasu
sangat menyukai golok, yang digunakan
jurumasak hebat di kastil hingga bilah pisau
kecil dengan ketajaman luar biasa untuk
memotong daging. Saat mengetahui keter-
tarikan Hisao pada segala macam peralatan,
diajaknya Hisao ke tempat penempaan besi
yang dibelinya; salah satu pandai besi, Koji,
membutuhkan asisten, dan Hisao mengasah
ketrampilannya bersama laki-laki itu. Hisao
menyukainya, bukan hanya pekerjaannya
dia memang terampil mengerjakannyatapi
juga karena pekerjaan itu memberinya lebih
banyak kebebasan, dan menjauhkannya dari
kehadiran Akio yang membuatnya merasa
tertekan. Sejak meninggalkan rumah, di-
pandangnya sang ayah dengan pandangan
baru. Ia sudah dewasa. Bukan lagi bocah
yang bisa didominasi dan dilecehkan. Pada
tahun baru nanti usianya beranjak tujuh
belas tahun.
Karena utang dan kewajiban, pekerjaannya
pada Koji dibayar dengan makanan dan
tempat tinggal, kendati Yasu sering mengaku
kalau dia tidak mengambil keuntungan apa
pun dari Pimpinan Kikuta, suatu ke-
hormatan diijinkan membantu. Namun
menurut Hisao, Yasu adalah orang yang
penuh perhitungan yang tidak mau memberi
dengan cuma-cuma: bila Yasu menolong
mereka sekarang, itu karena dia melihat akan
ada keuntungan di masa akan datang. Dan
Hisao juga melihat kalau Akio sudah
semakin tua, dan betapa kuno cara ber-
pikirnya, seolah sudah membeku selama
bertahun-tahun karena mengasingkan diri di
Kitamura.
Hisao menyadari bagaimana Akio merasa
tersanjung dengan perhatian Yasu, bahwa
ayahnya haus akan rasa hormat dan status
dengan cara yang hampir ketinggaian jaman
di kota yang sibuk dan moderen ini. Klan
Arai penuh dengan rasa percaya diri serta
kebanggaan. Wilayah mereka kini terbentang
melintasi wilayah Barat: Noguchi dan Hofu
milik mereka. Mereka mengendalikan pesisir
dan jalur kapal laut. Kumamoto dipenuhi
pedagangbahkan beberapa orang asing,
tidak hanya dari Shin dan Shilla, tapi juga,
kabarnya, dari Kepulauan Kecil Barat, orang
barbar dengan mata seperti buah ek serta
berjanggut lebat, dan barang-barang yang
indah tiada tara.
Kehadiran mereka di Kumamoto ditandai
dengan bisik-bisik karena seluruh kota tahu
larangan Otori yang tak masuk akal pada
siapa pun bertransaksi dengan orang asing
secara langsung: semua perdagangan harus
melalui pusat pemerintahan Klan Otori,
diatur dari Hofusatu-satunya pelabuhan
tempat kapal asing diijinkan secara resmi
merapat. Hal ini dipercaya banyak orang
begitu adanya karena Negara Tengah ingin
mengambil keuntungan bagi mereka sendiri,
begitu pula dengan berbagai penemuan, dan
begitu pula dengan masalah persenjataan
yang sangat efektif, sangat mematikan. Klan
Arai mulai membara di balik ketidakadilan.
Meskipun Hisao belum pernah melihat
orang barbar, tapi dia tertarik saat Jizaemon
memperlihatkan benda-benda mereka. Yasu
kerapkali memanggilnya ke tempat penempa-
an di sore hari untuk memberi perintah baru,
mengumpulkan persediaan baru pisau,
mengirim kayu untuk bagian pembakaran;
suatu hari dia ditemani laki-laki bertubuh
tinggi berpakaian mantel panjang dengan
tudung yang menutupi wajahnya. Mereka
tiba pada sore hari; matahari sudah mulai
tenggelam dan langit suram membawa
ancaman salju yang akan turun. Kala itu kira-
kira pertengahan bulan kesebelas. Hanya bara
api yang mewarnai bumi yang berubah dari
hitam menjadi abu-abu pada musim dingin.
Begitu tiba di jalanan, si orang asing
menyibakkan tudungnya dan Hisao
menyadari dengan terkejut dan keingin-
tahuan kalau itu orang barbar.
Orang barbar itu hampir tidak bisa
berbicara dengan merekadia hanya tahu
beberapa kata, tapi dia dan Koji adalah tipe
orang yang bicara dengan bahasa isyarat,
yang lebih memahami permesinan ketimbang
bahasa, dan selagi Hisao mengikuti mereka di
sekitar tempat penempaan, disadarinya kalau
ia juga seperti itu. Ia menangkap maksud si
orang barbar secepat Koji memahaminya.
Perhatian orang asing itu tersita oleh metode
mereka, mempelajari semuanya dengan
kilatan matanya yang cepat, menggambar
sketsa tempat pembakaran, tempat meniup
bara api, belanga, cetakan dan pipa; setelah
itu, ketika mereka minum sake, orang itu
mengeluarkan buku, dilipat dengan cara yang
aneh, dicetak, bukan ditulis, dan memper-
lihatkan gambar-gambar yang terlihat jelas
kalau itu cara-cara penempaan. Koji meng-
amatinya dengan cermat, dahinya berkerut,
jemarinya menggaruk-garuk belakang telinga.
Hisao, yang berlutut di satu sisi, mengintip
di bawah cahaya remang-remang, bisa me-
rasakan semangat dalam dirinya yang
semakin tinggi selagi halaman buku dibolak-
balik. Di benaknya muncul berbagai macam
kemungkinan yang bisa dilakukan. Pada
halaman terakhir ada beberapa senjata api:
sebagian besar senjata panjang dengan ben-
luk aneh yang sudah dikenalnya, tapi ada
satu, di bagian bawah halaman, terselip di
antara senjata yang lain bak seekor anak kuda
di antara kaki induknya. Bentuknya kecil,
hampir berukuran sepertiga dari panjang
semua senjata lainnya. Hisao tidak tahan
untuk mengulurkan dan menyentuh dengan
jari telunjuknya.
Si barbar tertawa cekikikan. "Pistola!" dia
membuat gerakan menyembunyikan senjata
itu di balik pakaian, lalu mengeluarkannya
dan mengarahkannya pada Hisao.
"Pa! Pa!" Dia tertawa. "Morto!"(=mati)
Hisao belum pernah melihat benda
seindah itu, dan segera menginginkannya.
Laki-laki itu menjentikkan jari, dan
mereka semua memahami maksudnya.
Senjata semacam itu mahal. Tapi bisa dibuat,
pikir Hisao, dan bertekad untuk mempelajari
cara membuatnya.
Yasu menyuruh Hisao pergi sewaktu dia
membicarakan soal pembayaran. Bocah itu
membereskan tempat penempaan, me-
madamkan api lalu menyiapkan semua
peralatan untuk keesokan harinya. Ia
membuat teh untuk orang-orang itu, lalu
mengisi mangkuk sake mereka kemudian
pulang, benaknya dipenuhi dengan berbagai
idetapi entah karena ide-ide itu, atau tidak
terbiasa dengan sake, atau angin dingin
setelah hawa panas di tempat penempaan
telah membuat kepalanya pening. Saat
sampai di rumah Yasu, yang terlihat olehnya
hanyalah separuh dari bangunan, hanya
separuh dari pajangan pisau dan kapak.
Hisao tersandung anak tangga, dan selagi
berusaha menyeimbangkan tubuh, dilihatnya
ibunya dalam kabut hampa tempat separuh
dari dunia berada.
Wajah ibunya tampak memohon dengan
penuh kelembutan dan ketakutan. Hisao
merasa mual sewaktu kekuatan meminta
bantuan perempuan itu menghantam diri-
nya. Rasa sakitnya makin tak tertahankan.
Tidak tahan untuk mengerang, kemudian
disadarinya kalau ia ingin muntah, jatuh
dengan tangan dan lutut menahan tubuh,
merangkak ke teras lalu membungkuk ke
parit.
Sake tadi terasa masam di mulutnya;
matanya berair karena rasa sakit, angin
sedingin es membuat air matanya terasa
membeku di pipinya.
Perempuan itu mengikutinya keluar
mengambang di atas tanah, garis bayangan
tubuhnya tersamar oleh kabut dan hujan
salju.
Akio, ayahnya, berseru dari dalam. "Siapa
di sana? Hisao? Tutup pintunya, dingin
sekali."
Ibunya bicara, suaranya di kepala Hisao
menyengat bak es. "Kau tidak boleh mem-
bunuh ayahmu."
Hisao tidak tahu kalau ia pernah ingin
melakukannya. Saat itu ia merasa ketakutan
kalau ibunya tahu semua vang ada di
benaknya, kebencian juga kasih sayangnya.
Perempuan itu berkata, "Aku takkan
membiarkanmu melakukannya."
Suara perempuan itu tidak bisa ditolerir
lagi, menggetarkan seluruh urat syaraf di
sekujur tubuhnya, membuat semua syarafnya
bak terbakar api. Hisao berteriak ke arah
perempuan itu. "Pergi! Tinggalkan aku
sendiri!"
Di sela-sela erangannya, disadarinya ada
yang mendekat, dan mendengar suara Yasu.
"Apa-apaan ini!" seru laki-laki itu,
kemudian memanggil Akio, "Ketua! Cepat
kemari! Putramu...."
Mereka membopongnya ke dalam dan
membersihkan muntahan dari wajah dan
rambutnya.
"Si bodoh ini minum terlalu banyak sake,"
kata Akio. "Seharusnya dia tidak boleh
minum. Kepalanya tidak kuat untuk itu.
Biarkan dia tidur."
"Hisao hampir tidak minum sake," sahut
Yasu. "Mestinya dia tidak mabuk. Mungkin
dia sakit?"
"Terkadang dia sakit kepala. Penyakitnya
itu sudah dideritanya sejak kecil. Tidak apa-
apa. Rasa sakitnya akan hilang dalam satu
atau dua hari."
"Anak malang, dibesarkan tanpa ibu!" ujar
Yasu, separuh bicara pada diri sendiri, selagi
membantu Hisao berbaring dan menyeli-
mutinya. "Dia menggigil kedinginan. Akan
kuseduh sesuatu untuk raembantunya tidur."
Hisao minum teh dan merasakan ke-
hangatan perlahan mulai kembali ke tubuh-
nya; menggigilnya berkurang, tapi rasa
sakitnya tidak berkurang, begitu pula dengan
suara perempuan itu. Kini perempuan itu
melayang di kamar yang gelapHisao tidak
perlu lentera untuk bisa melihatnya.
Mengerti samar-samar kalau ia mendengar-
kan perkataan perempuan itu maka rasa
sakitnya akan berkurang, tapi ia tak ingin
mendengarnya. Hisao menarik rasa sakit itu
di sekeliling dirinya sebagai tameng untuk
melawan perempuan itu, dan ingatan tentang
senjata api kecil yang indah tadi serta betapa
ia ingin membuatnya.
Rasa sakit membuatnya liar, bak hewan
yang disiksa. Membuatnya ingin melampias-
kannya pada orang lain.
Teh meredakan ambang batas kesadaran-
nya, dan ia pasti tertidur sebentar. Saat ter-
bangun, didengarnya Akio dan Yasu tengah
berbincang, mendengar dentingan mangkuk
sake dan suara pelan mereka selagi minum.
"Zenko sudah kembali," kata Yasu. "Aku
tidak bisa menahan perasaan kalau per-
temuan kalian akan membawa keuntungan
bagi semua orang."
"Itu tujuan utama kami keraari," sahut
Akio. "Bisakah kau mengatumya?"
"Aku yakin bisa. Zenko pasti sangat ingin
menyatukan keretakan antara Muto dan
Kikuta. Dan lagipula, kalian ada hubungan
kerabat dengan ikatan pernikahan, kan?
Putramu dan putra Zenko semestinya
saudara sepupu."
"Zenko memiliki kemampuan Tribe?"
"Bukan seperti yang diketahui banyak
orang. Dia seperti ayahnya, seorang ksatria.
Tidak seperti adiknya."
"Putraku hanya memiliki sedikit
kemampuan," aku Akio. "Dia pernah belajar
beberapa hal, tapi tak berbakat. Hal itu
membuat kalangan Kikuta kecewa. Ibunya
dulu sangatlah berkemampuan tinggi, tapi
dia tak mewariskan apa pun pada putranya."
"Tapi tangannya terampil. Koji cukup
menyanjung anak itudan Koji tak pernah
memuji siapa pun."
"Tapi itu tak membuatnya sebanding
dengan Otori."
"Itukah yang kau harapkan? Kalau Hisao
akan menjadi pembunuh agar bisa meng-
habisi Takeo?"
"Hidupku tidak akan damai sampai Otori
mati."
"Aku memahami perasaanmu, tapi Takeo
itu amat pandai sekaligus beruntung. Itu
sebabnya kau harus bicara dengan Zenko.
Sepasukan ksatria mungkin bisa berhasil
menggantikan kegagalan para pembunuh
Tribe."
Yasu minum lagi lalu tertawa terkekeh.
"Selain itu, Hisao menyukai senjata. Sepucuk
senjata lebih kuat ketimbang kekuatan magis
Tribe mana pun, bisa kupastikan itu.
Barangkali dia akan mengejutkanmu!"*
"Kau bilang dia mengancam anak-anak kita
secara terang-terangan?" Lady Arai menarik
baju luarnya yang terbuat dari bulu. Angin
bercampur hujan es yang berhembus dari
laut sepanjang minggu sejak kembalinya
mereka dari Maruyama akhirnya berubah
menjadi salju. Angin berhenti berhembus
dan serpihan salju mulai berjatuhan perl-
ahan dan mantap.
"Jangan khawatir," sahut suaminya,
Zenko. "Dia hanya menggertak. Takeo tak-
kan menyakiti mereka. Dia terlalu lemah
untuk melakukan hal itu."
"Di Hagi pasti sudah turun salju," ujar
Hana, seraya menatap ke laut di kejauhan
dan memikirkan anak-anaknya. Dia belum
bertemu dengan mereka lagi sejak mereka
pergi saat musim panas.
Zenko berkata, dengan niat buruk me-
warnai nada suaranya, "Dan di pegunungan;
dengan keberuntungan Takeo akan terjebak
di Yamagaia dan takkan bisa kembali ke Hagi
sebelum musim semi. Salju turun lebih awal
tahun ini."
"Setidaknya kita tahu Lord Kono sudah
aman dalam perjalanannya kembali ke
Miyako," komentar Hana, karena mereka
telah menerima pesan dari sang bangsawan
saat hendak meninggalkan Hofu.
"Mari berharap dia menyiapkan
penyambutan yang hangat bagi Lord Otori
tahun depan," ujar Zenko, lalu tawanya
meledak.
"Menyenangkan melihat Takeo terbuai
pujian," gumam Hana. "Kono memang
pendusta yang lihai dan patut dipercaya!"
"Seperti yang dikatakannya sebelum
pergi," komentar Zenko, "Jaring Surga amat-
lah luas, lubang jaringnya tipis. Kini jaring-
nya ditarik lebih kencang. Pada akhirnya
Takeo akan terjerat di dalamnya."
"Aku terkejut dengan kabar tentang
kakakku," ujar Hana. "Kukira dia sudah tak
bisa hamil lagi." Dibelainya permukaan bulu,
dan ingin merasakan di kulitnya. "Bagaimana
kalau nanti anaknya laki-laki?"
"Tak ada perbedaan besar, jika semuanya
berjalan sesuai tencana." sahut Zenko.
"Begitu pula halnya dengan perjodohan
antara Sunaomi dan putri mereka."
"Sunaomi tak boleh menikah dengan si
kembar!" ujar Hana. "Tapi kita akan pura-
pura menerima itu."
Mereka tersenyum dengan tatapan penuh
kelicikan.
"Satu-satunya hal baik yang pernah Takeo
lakukan yaitu menikahkanku denganmu,"
ujar Zenko.
Sedangkan bagi Takeo merupakan ke-
salahan fatal, pikir Hana. Andai dia menyerah
padaku dan mengambilku sebagai istri
keduanya, betapa berbedanya keadaan jadinya?
Aku bisa memberinya anak laki-laki; tanpa
diriku Zenko akan jadi tak lebih dari
bangsawan kecil, tidak menjadi ancaman bagi-
nya. Dia harus membayarnya. Begitu pula
dengan Kaede.
Hana tidak pernah memaafkan Takeo
karena telah menolak dirinya, sama halnya
dengan kakaknya karena menelantarkan diri-
nya ketika mereka masih kecil. Hana memuja
Kaede, bergantung padanya ketika kesedihan
akibat kematian orangtua mereka nyaris
membuat dirinya tidak warasdan Kaede
justru meninggalkannya, pergi menunggang
kuda pada satu pagi di musim semi dan tak
pernah kembali. Setelah itu, Hana dan
kakaknya, Ai, ditahan di Inuyama sebagai
sandera, dan akan dibunuh di sana andai
Sonoda Mitsuru tak menyelamatkan mereka.
"Kau masih bisa punya anak lagi!" seru
Zenko. "Ayo kita buat anak laki-laki lagi
sepasukan anak laki-laki."
Mereka hanya berdua di ruangan itu, dan
Hana mengira suaminya akan mulai bergerak
tapi kemudian, saat itu terdengar ketukan
ringan di pintu. Pintunya bergeser terbuka
dan seorang pelayan laki-laki bicara pelan,
"Lord Arai, Kuroda Yasu datang bersama
seorang laki-laki."
"Mereka datang dalam cuaca seburuk ini,"
ujar Zenko. "Sajikan minuman, tapi biarkan
mereka tunggu sebentar sebelum kau mem-
bawanya masuk, dan pastikan kelak kami
tidak diganggu."
"Kuroda datang secara terang-terangan?"
tanya Hana.
"Taku sedang di Hofutidak ada yang
memata-matai kita sekarang."
"Aku tak pernah suka pada Taku," kata
Hana tiba-tiba.
Tatapan tidak senang terpancar sekilas di
wajah Zenko yang lebar. "Dia adikku,"
Zenko memperingatkan istrinya.
"Seharusnya kesetiaannya yang pertama
mestinya kepadamu, bukan pada Takeo,"
hardik istrinya. "Dia menipumu setiap hari
tapi kau tidak memerhatikannya. Dia
memata-mataimu paling sering tahun ini,
dan bisa dipastikan kalau dia mengacaukan
surat-surat kita."
"Itu semua akan segera berubah," sahut
Zenko dengan tenang. "Kita akan bereskan
masalah penerus Muto. Taku kelak harus
mematuhiku, atau...."
"Atau apa?"
"Hukuman dalam Tribe atas ketidak-
patuhan adalah kematian. Aku tak bisa
mengubah peraturan itu bahkan untuk
saudara kandungku sendiri."
"Taku amat populer, kau sendiri sering
bilang begitu. Dan ibumu juga. Pastinya
banyak pihak yang tak ingin menentang
mereka?"
"Kurasa kita akan mendapatkan
dukungan. Dan jika teman Kuroda adalah
orang yang sudah kuperkirakan, sedikit
banyak akan cukup menambah kekuatan."
"Aku tak sabar ingin bertemu dengannya,"
Hana menaikkan alisnya.
"Sebaiknya kuceritakan sedikit tentang
dia. Namanya Kikuta Akio; dia ketua Kikuta
sejak kematian Kotaro. Menikah dengan
putri Kenji, Yuki; setelah istrinya mati, dia
bersembunyi dengan anak laki-laki Yuki."
Zenko berhenti sejenak lalu menatap Hana,
mata dengan kelopak tebalnya berbinar.
"Bukan anaknya Akio?" tanya Hana,
"Bukan anaknya Takeo, kan?"
Zenko mengangguk, lalu tertawa lagi.
"Sudah berapa lama kau tahu ini?" tanya
Hana. Dia terkejut sekaligus bersemangar
dengan tersingkapnya kenyataan ini, benak-
nya sudah mencari-cari cara untuk me-
manfaatkan berita ini.
"Aku mendengar semua desas-desus di
keluarga Muto sewaktu aku masih kecil.
Kenapa Yuki dipaksa minum racun? Alasan
Kikuta membunuhnya adalah pasti karena
mereka tak memercayainya. Dan kenapa
Kenji berpindah memihak Otori, bersama
empat dari lima keluarga? Kenji percaya
kelak Takeo akan mengakui anak itu, atau
setidaknya dengan melindunginya. Anak itu -
mereka memanggilnya Hisaoternyata anak
laki-laki Takeo."
"Kakakku pasti tak tahu, aku yakin itu."
Hana merasakan ada getar kesenangan
memikirkan hal itu.
"Mungkin kau bisa beritahukan pada saat
yang tepat," suaminya menyarankan.
"Oh, tentu." Hana sepakat. Tapi mengapa
Takeo tak pernah mencari anak itu?"
"Kurasa ada alasannya: dia tidak ingin
istrinya tahu, dan ketakutan kalau putranya
yang bisa membunuhnya. Sebagaimana
Tabib Ishida yang dengan baik hati meng-
ungkapkan pada kami, ada ramalan yang
mengatakan seperti itu, dan Takeo memer-
cayainya."
Hana bisa merasakan nadinya berdenyut
lebih kencang. "Saat kakakku tahu ini,
mereka pasti akan berpisah. Kaede sudah
bertahun-tahun menginginkan anak laki-laki:
maka dia takkan memaafkan Takeo karena
anak yang disembunyikan ini."
"Banyak laki-laki memiliki perempuan
simpanan dan anak haram, dan istri mereka
memaafkannya."
"Tapi kebanyakan istri bersikap seperti
diriku," sahut Hana. "Realistis dan praktis.
Bila kau punya perempuan simpanan, hal itu
tidak menggangguku. Aku memahami
kebutuhan dan hasrat laki-laki, dan tahu
kalau aku akan menjadi yang utama bagimu.
Kakakku adalah orang yang idealis: dia
percaya pada cinta. Takeo juga pasti begitu:
dia tak pemah mengambil perempuan lain
itu sebabnya dia tak punya anak laki-laki.
Lebih dari itu, keduanya dipengaruhi oleh
Terayama dan apa yang mereka sebut Ajaran
Houou. Pemerintahan mereka diseimbang-
kan dengan bersatunya mereka berdua:
dengan menyatukan laki-laki dan
perempuan. Berpisahnya kesatuan itu akan
membuat Tiga Negara hancur berantakan."
Hana menambahkan, "Dan kau akan
mewarisi semua yang telah diperjuangkan
ayahmu, dengan restu dari sang Kaisar, serta
dukungan dari jenderalnya."
"Dan Tribe takkan terpecah belah lagi,"
ujar Zenko. "Kita akan mengakui anak ini
sebagai pewaris dari keluarga Kikuta dan
Muto, dan melalui dirinya kita mengenda-
likan Tribe."
Hana mendengar langkah kaki di luar.
"Mereka sudah datang," katanya.
Suaminya meminta dibawakan sake lagi,
dan saat sudah datang, Hana menyuruh
pelayan pergi karena dia yang akan melayani
tamunya. Dia mengenal Kuroda Yasu yang
mengambil keuntungan dari barang-barang
mewah yang diimpornya dari Tenjiku,
gading dan emas. Ia pun memiliki beberapa
cermin yang terbuat dari kaca keras, berkilau
yang menunjukkan bayangan orang yang
nyata. Ia senang karena benda ini disimpan
di Kumamoto. Hana tak pernah memper-
lihatkannya di Hofu. Kini ia pun mem-
punyai rahasia hebat dan besar ini, rahasia
yang mengungkap siapa Takeo sebenamya.
Hana mengamati laki-laki itu, Akio. Laki-
laki itu melihat sekilas ke arahnya, kemudian
duduk dengan menunduk. Dari luar orang
itu kelihatan rendah hari, tapi segera ia tahu
kalau laki-laki itu bukanlah orang yang
rendah hati. Tubuhnya tinggi dan tegap;
walau usianya tidak muda lagi; dia kelihatan
sangat kuat. Memancarkan semacam ke-
kuatan, yang mambangkitkan secercah ke-
tertarikan dalam dirinya. Hana tidak suka
kalau laki-laki itu menjadi musuhnya, tapi
dia bisa menjadi sekutu yang kejam juga
tanpa belas kasihan.
Zenko memberi salam pada kedua tamu-
nya dengan sikap yang sangat sopan, ber-
usaha agar terlihat menghormati Akio sebagai
pimpinan Kikuta tanpa mengurangi status-
nya sendiri sebagai lord tinggi Arai.
"Tribe sudah terpecah belah begitu lama,"
tuturnya. "Aku sangat menyesalkan per-
pecahan ini, juga kematian Kotaro. Kini
Muto Kenji sudah tiada, maka sudah waktu-
nya luka-luka lama ini disembuhkan."
"Kurasa kita memiliki tujuan yang sama,"
sahut Akio. Cara bicaranya singkat, dengan
aksen Timur. Hana merasa kalau laki-laki itu
akan tetap diam ketimbang menggunakan
sanjungan, dan tidak mudah terpengaruh
dengan sanjungan, atau pun bentuk bujukan
lainnya.
"Kita bisa bicara dengan bebas di sini,"
ujar Zenko.
"Aku tak pernah menyembunyikan apa
yang paling kuinginkan," ujar Akio.
"Kematian Otori. Dia telah divonis mati oleh
Kikuta karena melanggar aturan Tribe, dan
juga atas pembunuhan Kotaro. Hal ini mem-
buat marah keluarga, nenek moyang dan
tradisi, serta dewa-dewa karena dia masih
hidup."
"Kabamya dia tidak bisa dibunuh,"
komentar Yasu. "Tapi yang pasti dia hanya
manusia biasa."
"Aku pernah hampir menggorok leher-
nya," Akio membungkuk, tatapan matanya
semakin tajam. "Aku masih tak mengerti
bagaimana dia bisa lolos. Dia memiliki
banyak keahlianseharusnya aku tahu; aku
yang melatihnya di Matsuedia lolos dari
semua usaha pembunuhan."
"Baiklah," kata Zenko perlahan, seraya
bertukar pandangan dengan Hana. "Aku
tahu sesuatu yang kau belum tahu. Hanya
beberapa orang yang mengetahuinya."
"Tabib Ishida yang mengatakannya pada
kami," ujar Hana. "Dia adalah tabib pribadi
Takeo, dan pernah mengobari banyak
lukanya. Dia tahu ini dari Muto Kenji."
Akio mengangkat kepala lalu menatap
langsung pada Hana.
"Takeo percaya kalau hanya putranya yang
bisa membunuhnya," lanjut Zenko. "Ada
semacam ramalan yang bisa dibuktikan."
"Seperti halnya Lima Pertempuran?" tanya
Yasu.
"Ya, dan ramalan itu digunakan untuk
membenarkan pembunuhan atas ayahku dan
keberhasilannya meraih kekuasaan," tutur
Zenko. "Kata-kata yang masih tetap di-
rahasiakan."
"Kendati demikian, Lord Takeo tidak
memiliki anak laki-laki" ujar Yasu seraya
menatap mereka semua secara bergantian.
"Meski ada hal-hal tertentu yang ter-
dengar..." Akio duduk dengan wajah tanpa
ekspresi. Hana merasakan lagi secercah
semangat.
Akio berkata pada Zenko, suaranya ter-
dengar semakin rendah dan keras. "Kau tahu
tentang putraku?"
Zenko agak menggerakkan kepala meng-
iyakan.
"Siapa lagi yang tahu tentang ramalan ini?"
"Terlepas dari semua orang yang ada di
ruangan ini dan Ishida: adikku,
kemungkinan juga ibuku, walaupun ibuku
tidak pernah mengatakannya padaku."
"Bagaimana dengan yang ada di
Terayama? Kubo Makoto mungkin juga
tahu: Takeo menceritakan segalanya kepada-
nya," gumam Hana.
"Mungkin juga. Intinya hanya sedikit
orang. Dan yang paling penting adalah
Takeo percaya itu," ujar Zenko.
Yasu meneguk cepat sake lalu berkata pada
Akio, "Jadi semua desas-desus itu benar?"
"Ya. Hisao adalah putra Takeo." Lalu Akio
menenggak minumannya, tampak seperti
tersenyum. "Anak itu tidak mengetahuinya.
Dia juga tidak memiliki keahlian Tribe. Tapi
kini aku tahu akan mudah baginya untuk
membunuh ayah kandungnya."
Yasu menepuk alas lantai dengan telapak
tangan terbuka. "Bukankah sudah kukatakan
kalau anak itu bisa saja mengejutkan dirimu?
Itu lelucon terbaik yang pernah ada selama
bertahun-tahun..."
Sekonyong-konyong keempat orang itu
tertawa gaduh.*
Kaede telah memutuskan untuk tinggal di
Hagi selama musim dingin sampai anaknya
lahir, dan Shizuka serta Ishida tinggal ber-
samanya. Mereka semua pindah dari kastil ke
rumah lama Lord Shigeru di tepi sungai:
rumah itu menghadap ke selatan, menangkap
semua sinar matahari musim dingin, dan
lebih mudah dibuat hangat selama hari-hari
yang panjang dan dingin. Chiyo masih
tinggal di sana, semakin bungkuk, usianya
sudah di ambang senja tapi masih mampu
menyeduh teh obat serta menceritakan
tentang masa lalu, dan apa yang dilupakan-
nya diisi oleh Haruka, tetap ceria dan
gamblang seperti dulu. Kaede mengundur-
kan diri dari publik. Takeo dan Shigeko
sudah pergi ke Yamagata; Maya dikirim
bersama gadis Muto, Sada, ke Maruyama,
kepada Taku; sedangkan Miki pergi ke desa
Tribe di Kagemura. Kaede senang memikir-
kan kalau ketiga putrinya sibuk dengan
pelatihan serius semacam itu, dan sering
mendoakan agar mereka mengembangkan
dan mengendalikan berbagai bakat yang
mereka miliki, dan agar dewa-dewi me-
lindungi mereka dari bahaya. Lebih mudah,
pikirnya sedih, menyayangi si kembar dari
jauh, saat kelahiran mereka yang tak wajar
dan bakat aneh bisa tak diacuhkan.
Kaede tidak kesepian karena selalu ada
yang menemani: Shizuka, kedua bocah, dan
juga hewan peliharaan putrinya, kera dan
anjing. Dengan ketidakhadiran ketiga putri-
nya, Kaede mencurahkan kasih sayangnya
pada keponakannya. Sunaomi dan Chikara
juga menikmati kepindahan itu, jauh dari
formalitas kehidupan di kastil. Mereka ber-
main di tepi sungai. "Seakan Shigeru dan
Takeshi hidup kembali," ujar Chiyo dengan
berlinang air mata selagi mendengarkan
teriakan anak-anak dari taman atau langkah
kaki mereka di atas nightingale floor. Kaede
merengkuh perutnya yang membuncit dan
memikirkan janin yang tumbuh di dalamnya.
Kelak putranya akan menjadi pewaris
Shigeru, pewaris sah Klan Otori.
Beberapa kali dalam seminggu Kaede
mengajak kedua anak itu ke biara. Ia telah
berjanji pada Shigeko untuk mengawasi
Tenba dan kirin. Ishida turut menemani
karena rasa sayangnya pada kirin kian
bertambah. Mori Hiroshi memberi pelana
dan tali kekang pada Tenba dan mengang-
kat Sunaomi ke pelana, lalu Kaede
menuntunnya berjalan mengelilingi padang
rumput. Kuda itu sepertinya mencium
sesuatu dari tubuhnya yang hamil dan senang
berjalan perlahan di samping Kaede, dengan
cuping hidung merekah, sesekali mengusap-
usap dengan hidungnya.
"Apa aku ini indukmu?" Kaede memarahi-
nya dengan lembut, sambil berdoa semoga
anak laki-lakinya akan sepemberani dan
setampan kuda itu. Kaede mengingat
kudanya, Raku, dan Amano Tenzo: kedua-
nya sudah lama tiada, namun roh mereka
akan tetap hidup selama ada kuda-kuda
Otori.
Kemudian Shigeko mengirim surat agar
kuda itu dikirim padanya karena telah
memutuskan untuk dihadiahkan kepada
ayahnya, seraya meminta ibunya agar tetap
merahasiakannya. Tenba segera dikirim ber-
sama pemuda pengurus kuda dengan naik
kapal ke Maruyama. Kaede dan Ishida men-
cemaskan kalau kirin akan panik saat
temannya pergi nanti. Kirin memang tampak
kurang bersemangat, tapi ini justru makin
meningkatkan rasa sayangnya pada teman
manusianya.
Kaede sering menulis, karena ia sangat
senang menulis membalas surat yang
ditujukan untuk suaminya; menulis surat
pada Shigeko dan Miki, mendesak mereka
belajar dengan rajin dan mematuhi guru;
kepada adik-adiknya, menceritakan pada
Hana tentang kesehatan serta kemajuan
kedua putranya dan mengundang mereka
datang pada musim semi.
Tapi Kaede tidak menyurati Maya karena
Maya tinggal di tempat rahasia di Maruyama,
dan adanya surat justru malah membahaya-
kan dirinya.
Kaede pergi ke biara lain; bekas rumah
Akane, dan mengagumi bentuk ramping dan
anggun dari patung kayu yang dikelilingi
rumah yang baru dibangun.
"Dia mirip Lady Kaede," ujar Sunaomi,
karena Kaede selalu memaksanya turut ke
tempat dia pernah dipermalukan dan
ketakutan. Sunaomi berhasil meraih kembali
kepercayaan dirinya, tapi Kaede masih
melihat sisa-sisa rasa malu dan luka yang
membekas, dan berdoa agar arwah sang dewi
muncul menyembuhkan segalanya.
Tak lama setelah Takeo pergi ke
Yamagata, Fumio kembali. Selama ketidak-
hadiran Takeo dan penarikan diri Kaede,
Fumio beserta ayahnya bertindak sebagai
wakilnya. Satu dari masalah yang meng-
ganggu dan alot adalah apa yang harus
dilakukan dengan kedatangan orang-orang
asing yang mengganggu dari Hofu.
"Bukannya aku tidak suka pada mereka,"
kata Fumio pada Kaede suatu sore pada
pertengahan bulan kesepuluh. "Seperti yang
kau tahu, aku sudah terbiasa dengan orang
asing; menikmati kehadiran mereka serta
menurutku mereka itu menarik. Tapi kian
hari kian sulit untuk tahu apa yang mesti
kulakukan. Mereka sangat gelisah; dan
kurang senang saat tahu Lord Otori tidak di
Hagi lagi. Mereka ingin bertemu dengannya;
mereka mulai tidak sabar. Aku sudah katakan
kalau aku tidak bisa memutuskan sampai
Lord Otori kembali ke Hagi. Mereka minta
penjelasan mengapa tidak boleh ke Yamagata
sendiri."
"Suamiku tak ingin mereka bepergian ke
seluruh penjuru negeri," sahut Kaede.
"Makin sedikit yang mereka tahu tentang
kita, makin baik."
"Aku setujudan aku tak tahu
kesepakatan apa yang mereka buat dengan
Zenko. Dia membiarkan mereka pergi dari
Hofu, tapi aku tidak tahu apa tujuannya.
Kuharap mereka mengirim surat yang dapat
mengungkap sesuatu, tapi jurubahasa mereka
tak bisa menulis sesuatu yang bisa dibaca
oleh Zenko."
"Ishida bisa menawarkan diri untuk men-
jadi jurutulis mereka," saran Kaede. "Itu bisa
membantumu agar tidak kesulitan menga-
caukan surat-surat mereka."
Mereka saling bertukar senyum.
"Mungkin Zenko hanya ingin menying-
kirkan mereka," lanjut Kaede. "Sepertinya
semua orang menganggap mereka sebagai
beban."
"Kendati demikian, banyak juga manfaat
yang bisa kita ambil dari merekailmu
pengetahuan dan kekayaan, selama mereka
bisa dikendalikan, bukan sebaliknya."
"Demi tujuan itu aku harus segera belajar
bahasa mereka," ujar Kaede. "Kau harus
bawa orang-orang asing itu dan juru-
bahasanya ke sini."
"Kegiatan itu tentu bisa memberi mereka
kesibukan sepanjang musim dingin," ujar
Fumio setuju. "Aku akan berikan kesan
betapa besar kehormatan bagi mereka bisa
diundang bertemu Lady Otori."
Pertemuan itu lalu diatur, dan Kaede me-
nemukan dirinya menanti dengan perasaan
takut: bukan karena orang-orang asing itu,
tapi karena ia tidak tahu bagaimana bersikap
pada jurubahasa mereka: anak dari keluarga
petani, perempuan dari rumah pelacuran,
pengikut kepercayaan Hidden, dan adik
perempuan suaminya. Kaede tak ingin ber-
hubungan dengan bagian hidup Takeo yang
satu ini. Ia tidak tahu apa yang harus
dikatakan pada orang seperti itu. Semua
nalurinya, ditambah dengan kehamilannya,
memperingatkan dirinya akan hal itu. Tapi ia
telah berjanji pada Takeo untuk mempelajari
bahasa orang asing, dan menemukan cara
lain.
Ia mengakui kalau dirinya juga ingin tahu:
terutama, katanya pada diri sendiri, tentang
orang-orang asing dan kebiasaan mereka, tapi
ia lebih ingin melihat seperti apa adik
perempuan Takeo.
***
Hal pertama yang terlintas di benaknya,
sewaktu Fumio menunjukkan jalan pada dua
laki-laki berbadan besar, diikuti oleh
perempuan bertubuh kecil, masuk ke dalam
ruangan, yaitu perempuan itu tidak mirip
suamiku. Ia yakin tak seorang pun akan men-
curigai hubungan tersebul. Kaede menyam-
but dengan bahasa resmi pada para laki-laki.
Mereka membungkuk hormat sambil berdiri,
sebelum Fumio memberitahu kalau mereka
seharusnya duduk.
Kaede duduk dengan punggung bersandar
ke dinding panjang ruangan itu, menghadap
ke beranda. Pepohonan yang tersentuh oleh
kepingan salju pertama terlihat begitu indah.
Hamparan daun-daun yang berwarna merah
tui berserakan di tanah, kontras dengan
bebatuan keabu-abuan serta warna lentera.
Di sebelah kanan Kaede, sebuah gulungan
kaligrafi hasil karyanya sendiri digantung di
ruang kecil yang terpisah. Isi gulungan itu
adalah puisl kesukaannya tentang belukar
semanggi di musim gugur, yang merupakan
asal nama kota Hagi. Kiasan pemandangan
yang indah itu amat memesona orang-orang
asing beserta jurubahasanya.
Orang asing itu duduk dengan canggung.
Mereka harus melepas alas kaki di luar, dan
Kaede memerhatikan sarung ketat yang
melekat di kulit yang menutupi kaki mereka.
Pakaian luar mereka aneh, berbentuk
gembung, membuat pinggul dan bahu
mereka kelihatan membesar. Bahannya ber-
warna hitam, dengan tambalan berwarna di-
jahitkan ke dalamnya: kelihatannya bukan
dari sutra, katun maupun rami. Perempuan
itu merangkak ke samping Kaede, kepalanya
menyentuh tikar, dan tetap menunduk.
Kaede mengamati secara sembunyi-
sembunyi pada kedua laki-laki tersebut, sadar
akan bau mereka yang terasa asing dengan
rasa jijik. Ia juga menyadari kalau pe-
rempuan di sampingnya itu memiliki tekstur
rambut dan warna kulit yang mirip Takeo.
Kenyataan itu membuat Jimtungnya ber-
debar kencang. Perempuan ini memang adik
suaminya. Sesaat Kaede mengira kalau ia
harus bereaksitak tahu apakah harus
menangis atau tak sadarkan diritapi
untungnya Shizuka datang dengan membawa
mangkuk teh dan kue kedelai manis. Kaede
berhasil mengendalikan dirinya lagi.
Perempuan itu, Madaren, justru lebih ter-
cengang. Dia menerjemahkan begitu pelan
dan tidak jelas hingga kedua pihak tidak tahu
apa yang diucapkannya. Mereka pura-pura
bertutur kata serta bersikap sopan; menerima
hadiah; kedua orang asing itu sering
tersenyumagak menyeramkandan Kaede
bicara selembut dan membungkuk seanggun
mungkin. Fumio sudah mengenai beberapa
kata bahasa orang asing itu, dan meng-
gunakan semuanya, sementara semua orang
mengatakan Terima kasih, Dengan senang
hari, dan maaf berulang kali dalam bahasa
mereka.
Status salah satu dari kedua orang itu, ber-
nama Don .loao, membingungkan: ksatria
sekaligus pedagang, Se-dangkan yang satu
lagi adalah pendeta. Butuh waktu lama
untuk bercakap-cakap karena Madaren
begitu khawatir akan menyinggung Lady
Otori. Dia bicara sangat berbelii-belit dan
penuh hormat. Setelah beberapa percakapan
yang panjang soal tempat tinggal dan ke-
butuhan orang-orang itu, Kaede menyadari
musim dingin mungkin berlalu tanpa ia bisa
belajar apa-apa.
"Ajak keluar dan perlihatkan taman pada
mereka," katanya pada Fumio. "Perempuan
ini tetap di sini bersamaku."
Kaede menyuruh semua orang pergi.
Shizuka menatap penuh tanya sewaktu
mengundurkan diri.
Para laki-laki kelihatannya cukup senang
bisa keluar, dan selagi mereka bicara dengan
keras tapi bernada ramah, mungkin mereka
bicara soal taman, Kaede mendekati
Madaren.
"Jangan takut. Suamiku sudah mencerita-
kan siapa dirimu. Sebaiknya tidak ada orang
lain yang tahu tentang ini. Demi suamiku
aku akan menghormati dan melindungimu."
"Keramahan Lady Otori terlalu agung bagi
orang seperti diriku," Madaren mulai bicara,
tapi Kaede menghentikannya.
"Aku ada satu permintaan padamudan
kedua laki-laki terhormat yang kau layani.
Kau telah mempelajari bahasa mereka. Aku
ingin kau mengajariku. Kita akan belajar
setiap hari. Kelak saat aku telah lancar bicara
bahasa itu, aku akan mempertimbangkan
semua permintaan mereka. Makin cepat aku
belajar, makin besar kemungkinan semua hal
itu dilaksanakan. Kuharap kau mengerti
maksudku. Salah satu dari mereka harus ikut
denganmu, karena aku juga harus belajar
tulisan mereka, tentunya."
"Aku hanyalah orang rendahan dari Was
yang terendah, tapi aku akan lakukan
semampuku untuk memenuhi keinginan
Lady Otori." Madaren menyembah lagi.
"Madaren," kata Kaede, mengucapkan
nama aneh itu untuk yang pertama kalinya.
"Kau akan menjadi guruku. Jangan terlalu
bersikap formal."
"Anda baik sekali," ujar Madaren. Dia ter-
senyum tipis saat duduk tegak.
"Kita akan mulai belajar besok," kata
Kaede.
***
Madaren datang setiap hari, menyeberangi
sungai dengan perahu dan berjalan melewati
jalan-jalan sempit ke rumah di tepi sungai.
Belajar setiap hari menjadi bagian dari
rutinitas kediaman itu, dan ia menyatu
dengan iramanya. Si pendetaDon Carlo
datang dua kali seminggu untuk mengajari
kedua perempuan itu menulis apa yang
disebutnya abjad, menggunakan kuas yang
paling tipis.
Rambut dan janggut kemerahan, serta
mata hijau biru pucat bak air laut, laki-laki
itu menjadi sasaran keingintahuan dan
keheranan. Dia biasanya datang dengan
dibuntuti anak-anak dan orang-orang dewasa
yang tidak punya hal lebih baik yang bisa
dikerjakan. Don Carlo juga sama ingin
tahunya, sesekali dia mendekati anak-anak
lalu memeriksa pakaian dan alas kaki mereka.
Dia juga mengamati setiap tanaman di
taman. dan sering mengajak Madaren pergi
ke sawah untuk bertanya pada para petani
tentang hasil panen dan musim. Dia
menyimpan banyak buku catatan, yang di
dalamnya dibuat daftar kata dan sketsa
bunga, pohon, bangunan dan alat pertanian.
Kaede melihat sebagian besar kegiatan ini
karena Don Carlo mengajak mereka berdua
sebagai sarana belajar bahasa, dan kerapkali
membuat sketsa untuk menjelaskan sebuah
kata. Orang itu benar-benar pandai, dan
Kaede malu sekaligus kagum karena saat
pertama kali bertemu ia berpikir kalau orang
ini hampir bukan manusia.
Bahasanya sulit: segala sesuatu yang
berkaitan dengan bahasa itu sepertinya
terbolak-balik, dan sukar untuk mengingat
bentuk maskulin dan feminin dan cara kata
kerjanya berubah. Suatu hari ketika Kaede
merasa putus asa, ia berkata pada Madaren,
"Aku takkan menguasai bahasa ini. Aku tak
tahu bagaimana kau mempelajarinya." Ini
menyakitkan hatinya: Madaren, perempuan
dari kalangan rendah dan tidak ber-
pendidikan, bisa begitu fasih menguasai
bahasa itu.
"Aku belajar dalam keadaan terpaksa,
bukan pilihan," sahut Madaren. Begitu sudah
bisa mengatasi rasa malu, sifat aslinya mulai
muncul. Percakapan mereka menjadi lebih
santai, terutama saat ada Shizuka. "Aku
membuat Don Joao mengajariku di tempat
tidur."
Kaede tertawa, "Kurasa suamiku tak
memikirkan itu."
"Don Carlo masih belum punya
pasangan," goda Shizuka. "Mungkin aku bisa
meniru caramu."
"Tampaknya Don Carlo tidak punya
hasrat terhadap perempuanataupun laki-
laki," kata Madaren. "Bahkan dia sama sekali
tidak menyetujuinya. Di matanya, bercinta
adalah yang disebutnya dosadan cinta
antar laki-laki khususnya, mengejutkan bagi-
nya."
Itu merupakan pemikiran yang baik
Shizuka maupun Kaede tidak terlalu me-
mahaminya.
"Barangkali saat aku sudah lebih me-
mahami bahasa mereka, Don Carlo akan
menjelaskannya," seloroh Kaede.
"Jangan pernah bicarakan hal semacam itu
dengannya," kata Madaren dengan nada
memohon. "Itu akan membuatnya sangat
malu."
"Pastinya begitu. Dia menghabiskan
banyak waktu untuk berdoa, dan acapkali
membaca dengan suara keras kitab sucinya
demi meraih kesucian dan pengendalian
nafsu dalam dirinya."
"Tidakkah Don Joao memercayai hal yang
sama?" tanya Shizuka.
"Sebagian dari dirinya percaya pada hal
yang sama, tapi hasratnya lebih kuat. Dia
memuaskan dirinya sendiri, kemudian
membenci dirinya karena hal itu."
Kaede penasaran apakah perilaku aneh ini
menular pada Madaren, tapi tak ingin
bertanya secara langsung. Kaede mengamati
lekat-lekat ketika kedua orang asing hadir,
dan berpikir kalau mereka berdua memang
membenci Madaren, meski mereka mem-
butuhkan keahlian dan bergantung
kepadanya. Kaede berpikir kalau hubungan
itu aneh dan terbolak-balik, dengan mani-
pulasi, bahkan eksploitasi, dari kedua belah
pihak. Kaede menemukan dirinya ingin tahu
tentang masa lalu Madaren, betapa aneh
perjalanan hidup yang telah membawa dia ke
tempat ini. Seringkali saat mereka hanya
berdua, ia berada di ambang keraguan untuk
bertanya pada Madaren bagaimana Takeo
ketika masih kecil. Namun pertanyaan ber-
sifat pribadi semacam itu bisa dianggap
terlalu mengancam.
Musim dingin tiba. Bulan kesebelas mem-
bawa hawa dingin yang menggigit; meskipun
sudah memakai baju berlapis-lapis dan ada
tungku batu bara agar tetap hangat. Kaede
tak berani lagi berlatih pedang bersama
Shizuka: kenangan buruk tentang keguguran
bayinya selalu melekat di benaknya, dan ia
sangat takut akan kehilangan bayinya ini.
Terbungkus karpet bulu, Kaede tak bisa
melakukan banyak hal selain belajar dan
bicara dengan Madaren.
Tepat sebelum rembulan di bulan
kesebelas muncul, surat berdatangan dari
Yamagata. Ia hanya berdua dengan Madaren;
Shizuka mengajak kedua cucunya pergi
melihat kirin. Kaede meminta maaf karena
menghentikan pelajaran kemudian segera
pergi ke ruang belajarnya sendiriruangan
tempat Ichiro membaca dan menulisdan
membaca surat-surat itu di sana. Takeo
menulis panjang lebaratau tepatnya
mendiktekan, karena dia kenal tulisan tangan
Minorutentang semua keputusan yang
telah diambil. Masih banyak persiapan yang
harus dibicarakan dengan Kahei dan Gemba
tentang kunjungan ke ibukota: Takeo masih
menunggu kabar dari Sonoda tentang peneri-
maan utusan pembawa pesan. Takeo merasa
berkewajiban untuk melewatkan Tahun Baru
di sana.
Kaede sangat kecewa: ia berharap Takeo
akan kembali sebelum salju menutup jalur
pegunungan. Kini ia merasa khawatir kalau
keberangkatan suaminya akan tertunda
hingga salju mencair. Ketika kembali pada
Madaren, perhatiannya teralihkan.
"Apakah Lady Otori mendapat kabar
buruk dari Yamagata?" tanya Madaren se-
waktu Kaede membuat kesalahan pelajaran
dasar untuk yang ketiga kalinya.
"Tidak juga. Semula aku berharap
suamiku akan kembali lebih awal, itu saja."
"Lord Otori baik-baik saja?"
"Kesehatannya baik-baik saja, terima kasih
Surga." Kaede berhenti sejenak lalu berkata,
"Kau memanggilnya dengan nama apa, saat
kalian masih kecil?"
"Tomasu, tuanku."
"Tomasu? Kedengarannya aneh sekali. Apa
artinya?"
"Itu nama salah satu guru besar di
kalangan Hidden." "Dan Madaren?"
"Madaren adalah perempuan yang, kata-
nya, mencintai putra Tuhan saat beliau
berjalan di bumi."
"Apakah putra Tuhan itu mencintai
perempuan itu?" tanya Kaede, seraya meng-
ingat-ingat percakapan mereka sebelumnya.
"Beliau mencintai kita semua," sahut
Madaren serius.
Saat itu ketertarikan Kaede bukanlah pada
kepercayaan orang Hidden, melainkan pada
suaminya yang tumbuh dewasa di
lingkungan mereka.
"Kurasa kau tak ingat banyak tentang
suamiku. Waktu itu kau pasti masih kecil."
"Dari dulu dia memang berbeda," tutur
Madaren perlahan. "Itu yang paling kuingat.
Wajahnya tidak mirip dengan kami se-
keluarga, dan sepertinya tidak berpikir
dengan cara yang sama. Ayahku sering marah
padanya; ibu pura-pura marah, tapi ibu
sayang sekali padanya. Aku selalu mengusik-
nya. Aku ingin dia memerhatikan aku.
Kurasa itu sebabnya aku mengenalinya se-
waktu bertemu di Hofu. Aku selalu
memimpikannya. Aku selalu memanjatkan
doa baginya."
Madaren terdiam, seolah takut sudah
terlalu banyak bicara. Kaede pun agak
terperanjat, meski ia tidak tahu apa sebabnya.
"Sebaiknya kita mulai lagi pelajaran kita,"
ujar Kaede dengan suara yang lebih tenang.
"Tentu saja, tuanku," sahut Madaren
patuh.
Malam itu salju turun dengan lebat, hujan
salju pertama tahun itu. Kaede terjaga di pagi
harinya dengan cahaya putih yang terasa
asing, dan hampir menangis. Karena itu
artinya jalan pasti sudah ditutup, dan Takeo
akan tetap di Yamagata sampai musim semi.
***
Kaede tertarik pada kedua orang itu, dan
semakin banyak mempelajari bahasanya, ia
semakin sadar harus tahu apa yang mereka
percayai, untuk bisa memahami mereka.
Don Carlo nampak juga bersemangat untuk
dapat membuat ia memahaminya. Ketika
akhirnya salju turun, laki-laki itu tidak bisa
ke sawah untuk melakukan penelitiannya,
maka dia makin sering datang bersama
Madaren dan percakapan mereka menjadi
lebih mendalam lagi.
"Don Carlo memerhatikan aku dengan
cara laki-laki normal memandang perem-
puan," komentarnya pada Shizuka.
"Mungkin dia harus diperingatkan tentang
reputasimu!" sahut Shizuka. "Pernah ada satu
saat ketika hasrat berarti kematian bagi laki-
laki mana pun!"
"Aku telah menikah enam belas tahun,
Shizuka! Kuharap reputasiku sudah dilupa-
kan. Lagipula itu bukan nafsu, karena kita
tahu Don Carlo tak merasakan desakan
semacam itu."
"Kita tidak pernah tahu itu! Kita hanya
tahu kalau dia tidak menanggapi hasratnya."
Shizuka menjelaskan. "Tapi bila kau mau
dengar pendapatku: kurasa dia berharap bisa
mengambil hatimu dengan agamanya. Dia
tak menginginkan tubuhmu; dia meng-
inginkan jiwamu. Dia sudah mulai bicara
tentang Deus, kan? Juga menjelaskan tentang
aga-ma di negaranya?"
"Sungguh aneh," ujar Kaede. "Apa
bedanya baginya atas apa yang kupercayai?"
"Mai, gadis yang kukirim untuk bekerja
pada mereka, mengatakan nama Lady Otori
sering disebut dalam perbincangan mereka.
Meskipun Mai belum memahami bahasa
mereka dengan sempurna, tapi dia merasa
kalau mereka berharap bisa mendapatkan
keuntungan dan pengikut dalam jumlah
yang sama besarnya, dan akhirnya men-
dapatkan wilayah baru bagi diri mereka
sendiri. Inilah yang mereka lakukan di
seluruh penjuru dunia."
"Dari apa yang mereka katakan, negeri
mereka sangat jauh dari sini: berjarak satu
tahun atau lebih dengan berlayar," tutur
Kaede. "Bagaimana mereka bisa hidup begitu
jauh dari rumah dalam waktu lama?"
"Kata Fumio itu adalah sifat dari semua
pedagang dan petualang. Membuat mereka
merasa sangat berkuasa, dan berbahaya."
"Baiklah, tapi aku tidak bisa membayang-
kan diriku mengikuti kepercayaan mereka."
Kaede membuang jauh-jauh pikiran itu
dengan sengit. "Bagiku itu seperti omong
kosong!"
"Semua kepercayaan bisa kelihatan seperti
kegilaan," sahut Shizuka. "Tapi bisa tiba-tiba
menjangkiti manusia, seperti wabah. Aku
pernah melihatnya. Waspadalah."
Kata-kata Shizuka membuat Kaede ter-
ingat saat dirinya menjadi istri Lord
Fujiwara, dan bagaimana ia melalui hari-hari
yang panjang dalam doa dan puisi, me-
megang semua janji yang telah dikatakan
padanya sementara dirinya terbaring dalam
sihir tidur Kikuta seolah masuk ke peti es.
Bersabarlah: dia akan menjemputmu.
Kaede merasa bayinya menendang dalam
perutnya. Kini seluruh kesabarannya sudah
hampir habis dengan kehamilannya, salju
serta ketidakhadiran Takeo.
"Ah, punggungku sakit," katanya seraya
menghcla napas.
"Mari kupijat. Membungkuk." Selagi
Shizuka memijat, dia diam saja; dan
kesunyian itu semakin senyap seakan dia
tenggelam dalam lamunan.
"Apa yang kau pikirkan?" tanya Kaede.
"Hantu-hantu dari masa lalu. Dulu aku
suka duduk bersama Lord Shigeru tepat di
ruangan ini. Beberapa kali aku membawa
pesan dari Lady Maruyama: kau tahu kalau
dia adalah salah satu pengikut."
"Ajaran kaum Hidden," ujar Kaede.
"Kurasa agama orang asing itu, meski tampak
sama, tapi lebih dogmatis dan tidak
mengenai kompromi."
"Semakin menguatkan alasan untuk mem-
perlakukannya dengan curiga!"
Selama musim dingin, Don Carlo
memperkenalkannya lebih banyak kata:
neraka, hukuman, kutukan, dan ia ingat apa
yang pernah Takeo katakan tentang Tuhan
yang Maha Melihat milik kaum Hidden dan
tatapannya yang tanpa ampun. Kaede
menyadari betapa Takeo telah memilih
menghindari tatapan itu, dan itu makin
membuat ia makin mengagumi dan men-
cintai suaminya.
Karena tentu saja dewa atau tuhan itu
baik, dan menginginkan kehidupan berjalan
dengan selaras bagi semua mahkluk, musim
berlalu, malam berganti siang dan musim
panas berganti dengan musim dingin, dan
seperti ajaran Sang Pencerah, kematian itu
tak lebih hanya pemberehentian sejenak
sebelum kelahiran selanjutnya....
Kaede berusaha menjelaskan hal ini pada
Don Carlo dengan kosa katanya yang ter-
batas. Saat tidak berhasil dengan kata-kata,
diajaknya laki-laki itu melihat pahatan
patung Kannon Sang Maha Pengampun
yang sudah selesai di kuil yang telah di-
bangun untuknya.
Saat itu cuaca terasa lembut di awal musim
semi. Hunga-bunga plum masih ber-
gelantungan bak serpihan salju di ranting
tanpa daun di taman Akane; salju di bawah
telapak kaki terasa lembap dan mencair.
Kendati tidak suka dengan caranya diantar,
Kaede dibawa dalam tandu; kehamilannya
sudah berusia tujuh bulan dan diperlambat
dengan berat bayi yang dikandungnya. Don
Carlo juga dibawa dengan tandu terpisah di
belakangnya, dan Madaren mengikutinya.
Para tukang kayu, di bawah pengawasan
Taro, tengah memberi sentuhan akhir pada
kuil, memanfaatkan cuaca vang lebih hangat.
Kaede senang melihat bangunan baru itu bisa
bertahan menghadapi musim dingin, dengan
dinaungi atap rangkap dua, keseimbangan
sempurna pada kedua lengkungannya seperti
yang Taro janjikan. Bentuk bangunan itu
mencuat ke atas dan dipantulkan dengan
dedaunan pinus yang membentuk seperti
payung pelindung. Salju masih menempel di
atap, menyilaukan saat icrkena pantulan
cahaya matahari; tetesan air yang membeku
mulai mencair dari tepi atap, membiaskan
cahaya.
Jendela kecil di atas pintu samping ber-
bentuk seperti daun, dan hasil karya seni
ukiran yang amat halus mem-biarkan cahaya
matahari masuk. Pintu utama terbuka lebar,
dan sinar matahari musim dingin jatuh
menyirami lantai yang baru. Kayunya ber-
warna seperti madu dan berbau semanis
madu pula.
Kaede memberi salam pada Taro, lalu
melepas sandal di beranda.
"Orang asing ini tertarik pada karyamu,"
katanya pada Taro, dan melihat ke belakang-
nya tempat Don Carlo dan Madaren men-
dekati bangunan kuil.
"Selamat datang," sambut Kaede pada si
pendeta dengan bahasa orang itu. "Ini
tempat istimewa untukku. Masih baru.
Orang ini yang membuatnya."
Taro membungkuk, dan Don Carlo mem-
buat gerakan canggung dengan kepala.
Orang itu terlihat lebih gelisah dari biasanya,
dan saat Kaede berkata, "Mari masuk. Kau
harus lihat karya paling indah dari orang ini,"
si pendeta menggeleng lalu menyahut, "Aku
lihat dari sini saja."
"Tapi kau tak bisa melihatnya dari sini,"
desak Kaede, kemudian Madaren berbisik,
"Dia takkan masuk; ini bertentangan dengan
kepercayaannya."
Kaede merasa marah atas sikap kasar laki-
laki itu, ia tak bisa memahami alasan di
baliknya, tapi ia tak menyerah begitu saja. Ia
sudah mendengarkan Don Carlo sepanjang
musim dingin, dan sudah belajar banyak
darinya. Kini giliran orang itu yang harus
mendengarkan.
"Ayolah," kata Kaede. "Lakukan seperti
yang kuminta."
"Pasti menarik," saran Madaren kepada-
nya. "Kau bisa lihat bagaimana konstruksi
bangunan ini dan bagaimana pahatan kayu-
nya."
Don Carlo melepas alas kaki dengan sikap
enggan yang sengaja diperlihatkan. Taro
membantunya dengan senyum yang mem-
beri semangat. Kaede melangkah ke dalam
kuil; patung yang sudah selesai berdiri di
depan mereka. Satu tangan, menekan dada,
memegangi bunga teratai; sedangkan tangan
yang satu lagi menyibak keliman jubah
dengan dua jari yang ramping. Lipatan jubah
itu dipahat sangat halus hingga terlihat
seperti bergoyang saat tertiup angin sepoi-
sepoi. Mata sang dewi menatap ke bawah,
ekspresinya tegas sekaligus penuh welas asih,
senyum dengan bibir agak mencuat ke atas.
Kaede menangkupkan telapak tangan lalu
menunduk berdoauntuk bayi dalam
kandungannya, untuk suami dan ketiga
putrinya, dan untuk arwah Akane yang
mungkin pada akhirnya bisa istirahat dengan
tenang.
"Dia cantik sekali," kata Don Carlo,
dengan semacam rasa ingin tahu, tapi tidak
berdoa.
Kaede mengatakan pada Taro betapa si
orang asing mengagumi patungnya, melebih-
lebihkan pujiannya untuk menebus sikap
kasarnya tadi.
"Keahlianku biasa saja. Tanganku men-
dengarkan apa yang ada di dalam kayu, dan
membantunya menemukan jalan keluamya,"
sahut Taro.
Kaede berusaha menerjemahkan kalimat
ini sebisa mungkin. Taro, dengan gerakan
dan sketsa gambar, memperlihatkan pada
Don Carlo konstruksi bagian dalam atap,
bagaimana penyangganya saling menopang.
Kemudian Don Carlo mengeluarkan buku
catatan lalu menggambar apa yang dilihat-
nya, menanyakan tentang nama kayu, dan
nama setiap sambungan.
Matanya kerapkali menerawang kembali
ke arah sang dewi, kemudian ke arah wajah
Kaede.
Sewaktu mereka pergi, Don Carlo ber-
gumam, "Kurasa aku tidak bisa menemukan
Bunda Maria dari Timur."
Itulah pertama kalinya Kaede mendengar
kata itu, dan tak mengerti artinya, namun
melihat ada sesuatu yang telah meningkatkan
ketertarikan Don Carlo pada dirinya; hal itu
mengganggunya; merasakan tiba-tiba bayi
dalam perutnya menendang keras, dan ingin
sekali agar Takeo kembali.*
Sisa luka cakaran membekas di wajahnya
sudah hampir memudar ketika Takeo
kembali ke Hagi di akhir bulan ketiga. Salju
belum lagi mencair: musim dingin berlang-
aing lama dan sulit. Dengan ditutupnya
semua perbatasan antar kota di seluruh Tiga
Negara, ia tidak bisa menerima surat, dan
kecemasannya terhadap Kaede makin
menjadi-jadi. Takeo senang Ishida tinggal
bersama istrinya selama masa kehamilanya,
namun juga menyesali ketidakhadiran si
tabib selagi cuaca yang tak bersahabat mem-
buat luka lamanya terasa makin sakit,
sedangkan minuman penenang telah habis.
Takeo terpaksa menghabiskan waktu ber-
sama Miyoshi Kahei, membahas strategi
untuk musim semi yang akan datang serta
kunjungan ke ibukota, dan membaca catatan
administrasi Tiga Negara. Kedua hal itu
membangkitkan semangatnya: merasa siap
untuk apa saja yang akan terjadi saat
kunjungan nanti. Ia akan pergi dengan
damai, namun takkan meninggalkan
negerinya tanpa penjagaan. Dan catatan
administrasi memastikan sekali lagi seberapa
kuat negaranya, sampai ke tingkat desadi
mana pemimpinnya dipilih oleh para
petanidapat dimobilisasi untuk mem-
pertahankan diri mereka dan wilayahnya.
Musim semi tiba dan ia langsung me-
mutuskan untuk pulang. Saat menunggang
kuda melewati pedesaan, semua itu kian
memantapkan hatinya. Tenba melewati
musim dingin dengan baik, hampir tidak
berkurang berat badan maupun kondisinya.
Bulu musim dinginnya telah disikat bersih
oleh bocah-bocah pengurus kuda, dan tubuh
hitamnya berkilauan bak pernis. Gembira
karena berada di jalanan, menuju tempat
kelahirannya, membuat kuda itu melompat
dan berjingkrak, cuping hidungnya mengem-
bang, surai dan ekornya melambai-lambai.
***
"Apa yang terjadi pada wajahmu?" tanya
Kaede ketika mereka hanya berdua,
menyelujuri tanda bekas luka yang mulai
menghilang dengan jari-jarinya.
Takeo tiba tadi pagi. Udara masih terasa
dingin, angin segar; jalanannya berlumpur,
seringkali tergenang. Ia langsung ke rumah
lama, tempat Chiyo dan Haruka menyam-
butnya dengan suka cita, mandi dan makan
bersama Kaede, Ishida serta kedua bocah.
Saat ini ia dan Kaede duduk di kamar lantai
atas, penutup jendela terbuka, percikan
sungai terdengar di telinga mereka, dan di
mana-mana tercium aroma musim semi.
Bagaimana mengatakannya? Takeo me-
natap istrinya dengan penuh kekhawatiran.
Waktu melahirkan hampir tiba, tidak lebih
dari tiga atau empat minggu lagi. Teringat
olehnya apa yang Shigeko katakan: Ayah
harus ceritakan pada Ibu. Ayah seharusnya
tidak menyimpan rahasia dari Ibu. Ceritakan
semuanya pada Ibu.
Takeo berkata, "Aku tak sengaja menabrak
dahan. Tidak apa-apa."
"Kelihatannya seperti dicakar. Aku tahu,
kau kesepian di Yamagata lalu menemukan
perempuan yang menggairahkan!" Kaede
menggodanya, senang suaminya sudah
berada di rumah lagi.
"Tidak," sahutnya dengan nada lebih
serius. "Aku sudah sering mengatakan pada-
mu, aku tidak akan tidur dengan siapa pun
selain dirimu."
"Seumur hidupmu?"
"Seumur hidupku."
"Bahkan kalau aku mati lebih dulu?"
Ditempelkan jarinya dengan lembut ke
bibir istrinya. "Jangan bilang begitu."
Ia merengkuh Kaede dan memeluknya
erat-erat sesaat tanpa sepatah kata pun.
"Ceritakan semuanya," akhirnya Kaede
berkata. "Bagaimana Shigeko? Aku sangat
gembira memikirkan dia sebagai Lady
Maruyama saat ini."
"Shigeko baik-baik saja. Andai kau bisa
melihatnya saat upacara. Dia mengingatkan-
ku pada Naomi. Tapi saat itu baru kusadari
kalau Hiroshi jatuh cinta padanya."
"Hiroshi? Tidak mungkin. Dia selalu
memperlakukannya sebagai adik. Apakah dia
bilang begitu?"
"Tidak dengan kata-kata. Tapi aku yakin
itu sebabnya dia selalu menghindari per-
nikahan."
"Dia berharap menikah dengan Shigeko?"
"Menurutku Shigeko juga menyayangi-
nya."
"Shigeko masih gadis kecil!" ujar Kaede,
kedengaran seolah marah dengan pendapat
seperti itu.
"Usianya sama dengan kau saat kita
bertemu," Takeo memperingatkan.
Sesaat mereka saling pandang. Lalu Kaede
berkata, "Mereka tidak boleh berada di
Maruyama bersama-sama. Jangan terlalu
banyak berharap dari mereka berdua!"
"Hiroshi jauh lebih tua ketimbang diriku
saat itu! Kuyakin dia lebih bisa mengendali-
kan diri. Dan mereka tak berharap hidup
mereka berakhir dalam hitungan jam." Cinta
kita pun merupakan hasrat yang buta,
pikirnya. Kita belum terlalu mengenal satu
sama lain. Kita dirasuki kegi-laan yang begitu
kuat hingga mengakibatkan terjadinya pem-
bunuhan yang tiada henti. Shigeko dan
Hiroshi sudah seperti kakak adik. Bukan dasar
yang buruk untuk sebuah pernikahan.
"Kono mengisyaratkan persekutuan politis
melalui pernikahan dengan jenderal Kaisar,
Saga Hideki," tuturnya pada Kaede.
"Pendapat yang tidak bisa kita abaikan
begitu saja," sahut Kaede, menghela napas
panjang. "Aku yakin Hiroshi bisa menjadi
suami yang baik, tapi pernikahan semacam
itu akan menyiakan-nyiakan Shigeko, dan
tidak memberi keuntungan yang sebenarnya
belum kita miliki."
"Baiklah, Shigeko akan ikut bersamaku ke
Miyako; kami akan bertemu dengan Saga
dan memutuskan nanti."
Takeo meneruskan ceritanya tentang
kelanjutan masalah dengan Zenko. Mereka
memutuskan untuk mengundang Hana saat
musim panas agar bisa bertemu kedua
putranya dan menemani Kaede setelah
melahirkan.
"Dan kuharap kau sudah fasih bicara
dengan bahasa yang baru," ujar Takeo.
"Aku sudah membuat kemajuan," sahut
Kaede. "Don Carlo maupun adikmu adalah
guru yang baik."
"Adikku baik-baik saja?"
"Secara umum, ya, baik-baik saja. Kami
terserang flu, tapi tidak serius. Aku suka
padanya: kelihatannya dia baik dan pandai,
meskipun tidak mendapat pendidikan."
"Dia mirip ibuku," ujar Takeo. "Apakah
orang-orang asing itu berhubungan dengan
Hofu atau Kumamoto?"
"Ya, mereka sering menulis surat. Ishida
kadang membantu mereka, dan sudah
sewajarnya kami membacanya."
"Kau memahami semua isinya?"
"Sulit sekali. Bahkan bila sudah mengenal
setiap kata, aku masih saja kesulitan me-
nangkap maknanya. Aku harus sangat ber-
hati-hati agar tidak membuat Don Carlo
takut: laki-laki itu amat tertarik dengan
semua yang kukatakan, dan menimbang-
nimbang setiap perkataan. Dia menulis
banyak hal tentang diriku, pengaruhku pada
dirimu, kekuatan yang tidak biasa sebagai
seorang perempuan." Sesaat Kaede terdiam.
"Menurutku dia ingin aku masuk agamanya,
dan meraih dirimu melalui aku. Madaren
pasti sudah menceritakan kalau kau lahir di
antara kaum Hidden. Don Carlo nyaris
mengira kau adalah pengikut ajaran mereka
sehingga akan diberi ijin menyebarkan
agama, sedangkan Don Joao diijinkan ber-
dagang di Tiga Negara."
"Perdagangan itu masalah lain: boleh
selama kita bisa mengendalikannya dan demi
kepentingan kita. Tapi tak akan kuijinkan
dia menyebarkan agama, atau bepergian."
"Tahukah kau kalau sudah ada orang asing di
Kumamoto?" tanya Kaede. "Don Joao
menerima sepucuk surat dari salah satunya.
Mereka adalah kenalan bisnis, sepertinya,
dari kampung halaman mereka.''
"Aku sudah curigai." Takeo menceritakan
tentang cermin yang diperlihatkan kepada-
nya di Maruyama.
"Aku juga punya cermin yang sama!"
Kaede memanggil Haruka, dan pelayan itu
membawakan cermin itu, terbungkus kain
sutra tebal.
"Ini pemberian Don Carlo," tutur Kaede,
seraya membuka bungkusnya.
Takeo mengambilnya dan bercermin. Ia
merasa aneh dan terkejut.
"Hal ini mencemaskanku," kata Takeo.
"Apa lagi yang diperdagangkan dari Kuma-
moto yang kita belum tahu?"
"Satu lagi alasan yang tepat agar Hana
berada di sini," kata Kaede. "Dia tidak tahan
untuk memamerkan barang-barang baru
kepunyaannya dan akan mengumbar tentang
kehebatan Kumamoto. Aku yakin bisa me-
mancingnya agar bercerita lebih banyak lagi."
"Shizuka tidak ada di sini? Aku ingin
bicara dengannya tentang masalah ini, dan
mengenai Zenko."
"Dia ke Kagemura begitu salju mencair.
Aku mencemaskan Miki dalam cuaca dingin
seperti ini, dan Shizuka punya masalah yang
harus dibicarakan dengan keluarga Muto."
"Miki akan kembali bersamanya?" Takeo
terperangkap oleh kerinduan ingin bertemu
dengan putri bungsunya.
"Belum diputuskan." Kaede menepuk Kin,
anjing yang berbaring meringkuk di
sampingnya. "Kin pasti senang saat Maya
pulangdia merindukan si kembar. Kau
bertemu Maya?"
"Ya, aku bertemu." Takeo tak yakin bagai-
mana meneruskannya.
"Kau juga mengkhawatirkannya? Dia baik-
baik saja?"
"Maya baik-baik saja. Dia sedang belajar
pada Taku. Dia tengah belajar mengendali-
kan diri dan juga disiplin. Tapi Taku seperti-
nya tergila-gila pada gadis itu."
"Dengan Sada? Apa semua laki-laki sudah
gila? Sada! Dia orang terakhir yang kuduga
bisa membuat Taku mabuk kepayang.
Kukira gadis itu tidak peduli pada laki-laki
dia berpenampilan seperti laki-laki."
"Seharusnya tidak kuceritakan padamu,"
sahut Takeo. "Jangan sampai masalah ini
membuatmu tertekan. Kau harus memikir-
kan kesehatanmu."
Kaede tertawa. "Aku lebih merasa terkejut
ketimbang tertekan. Selama tidak meng-
ganggu tugas mereka, biarkan saja mereka
saling mencinta. Tak ada ruginya, kan?
Hasrat seperti itu tidak bisa dihentikantoh,
nanti akan padam dengan sendirinya."
"Hasrat kita tak pernah padam," sahut
Takeo.
Kaede meraih tangan suaminya dan
menaruhnya di perutnya.
"Putra kita sedang menendang," katanya,
dan Takeo merasakan si bayi bergerak kuat
dalam perut istrinya.
"Sebenarnya aku tidak ingin membicara
kannya," kata Takeo. "Tapi kita harus me-
mutuskan nasib sandera yang kita tahan di
Inuyama, keluarga Kikuta yang menyerang-
mu tahun lalu. Ayah mereka sudah mati
dibunuh tahun lalu, dan aku ragu kalau
Kikuta mau berunding. Keadilan menuntut
kalau mereka dihukum mati atas kejahatan
yang mereka lakukan. Kukira sudah wakt-
unya menulis surat pada Sonoda. Harus
kelihatan sesuai hukum, bukan sebagai
tindakan balas dendam. Mungkin aku harus
ke sana uniuk menyaksikannyaaku mem-
pertimbangkan untuk meminta hukuman
dilaksanakan saat aku melewati Inuyama
dalam perjalanan ke ibukota."
Kaede gemetar. "Itu pertanda buruk untuk
suatu perjalanan. Katakan pada Sonoda
untuk melakukannya sendiri: dia dan Ai
adalah wakil kita di Inuyama. Mereka bisa
mewakili kita. Dan harus laksanakan
secepatnya. Jangan ditunda."
"Minoru akan menulis suratnya sore ini."
Takeo berterima kasih pada Kaede atas
keputusannya yang tegas.
"Oh ya, Sonoda baru saja menulis surat.
Kurirmu sudah kembali ke Inuyama. Mereka
diterima Kaisar. Mereka diberi penginapan
oleh Lord Kono selama musim dingin, dan
dia selalu memujimu dan Tiga Negara."
"Tampaknya sikap Kono berubah," sahut
Takeo. "Dia tahu cara memikat serta
memuji. Aku tidak memercayai dia, tapi aku
harus tetap pergi ke Miyako sesuai rencana."
"Alternatif lain terlalu menakutkan untuk
dipikirkan," gumam Kaede.
"Kau pasti paham benar apa alternatif itu."
"Tentu: menyerang dan mengalahkan
Zenko dengan cepat di Barat dan bersiap
melawan Kaisar di Timur. Pikirkan biaya
yang dibutuhkan. Bahkan jika kita bisa
memenangkan kedua wilayah, kita membawa
dua pertiga negara kita dalam kancah
peperangandan akan menghancurkan
kerabat sendiri dan merenggut Sunaomi dan
Chikara dari orangtuanya. Ibu mereka adalah
adikku, dan aku sayang padanya dan anak-
anaknya."
Takeo menarik tubuh Kaede lebih dekat,
dan mengecup tengkuk istrinya, bekas luka
itu masih tetap kelihatan.
"Takkan kubiarkan hal itu tcrjadi. Aku
janji."
"Tapi kekuatan yang tengah digalang
dimana dirimu, suamiku sayang, tidak bisa
mengendalikannya." Kaede membenamkan
diri dalam pelukan Takeo. Napas mereka
makin memburu dan keduanya larut menjadi
satu kesatuan.
"Kuharap kita bisa seperti ini selamanya,"
kata Kaede pelan. "Aku sangat bahagia saat
ini; tapi aku takut apa yang akan terjadi
kelak."
***
Semua orang menantikan bayi itu lahir, tapi
sebelum Kaede dipingit, Takeo ingin
bertemu dengan kedua orang asing. Ia ingin
mencapai persetujuan yang memuaskan
kedua belah pihak untuk masalah
perdagangan dan memperingatkan mereka
siapa penguasa Tiga Negara. Takeo khawatir
kalau selama ia tidak ada di sana, saat Kaede
sibuk dengan bayinya, orang-orang asing itu
akan berpaling ke Kumamoto untuk men-
dapatkan akses ke distrik lain, dan sumber
daya lain.
Cuaca hari itu semakin hangat; daun
ginkgo dan maple merekah, cerah dan segar.
Seketika bunga ceri bermekaran di mana-
mana, gunung berwarna putih bersih. taman
berwarna merah muda. Burung kembali ke
sawah yang berair, dan suara katak
memenuhi udara. Bunga aconitus dan violet
bermekaran di hutan dan taman, diikuti
dandelion, windflower, aster dan vetch. Jerit
jangkrik mulai terdengar, dan kicau burung
warbler mengalun indah.
Don Carlo dan Don Joao datang bersama
Madaren ke penemuan yang diadakan di
ruang utama yang menghadap taman. Aliran
sungai dan air terjun di taman memercikkan
air dan ikan carp merah keemasan berenang
dengan malas di kolam, sesekali melompat
untuk menangkap serangga musim semi.
Takeo sebenarnya lebih senang menerima
mereka di kastil dengan upacara megah, tapi
ia tak ingin Kaede melakukan perjalanan.
Kaede harus hadir untuk membantu men-
jelaskan maksud kedua belah pihak.
Itu tugas yang berat. Kedua orang asing itu
kini lebih mendesak. Mereka tak sabar untuk
memulai perdagangan yang sesungguhnya,
meskipun tidak menyatakannya secara
terang-terangan. Madaren lebih gelisah
dengan adanya Takeo. Dia tampak takut
menyinggung, tapi juga ingin membuatnya
terkesan. Ia pun gelisah, mencurigai kedua
orang asing itu, karena mereka seperti
memandang rendah dirinya, tahu kalau
Madaren adalah adiknyaapakah mereka
memang tahu itu? Apakah adiknya telah
mengatakannya pada mereka? Kaede
mengatakan mereka tahu kalau ia lahir di
kalangan Hidden... penerjemahan semakin
memperlambat pembicaraan; sore segera
menjelang.
Takeo meminta mereka menyatakan
dengan jelas keinginan mereka. Don Joao
menjelaskan bahwa mereka berharap bisa
membangun hubungan dagang secara ter-
atur. Dia memuji sutra, kerang mutiara, dan
keramik dan porselen yang diimpor dari
Shin. Semua ini, katanya, banyak dicari dan
bernilai tinggi di negaranya. Sebagai imbalan,
dia menawarkan perak, pecah belah, rempah
dan kayu wangi, dan tentunya senjata api.
Takeo menjawab bahwa semua ini bisa
diterima: satu-satunya syarat yaitu adalah
semua itu harus dilakukan melalui Hofu dan
di bawah pengawasannya, dan senjata api
hanya bisa masuk dengan seijin dirinya atau
istrinya.
Kedua orang itu saling bertukar pandang
ketika syarat itu diterjemahkan, dan Don
Joao menjawab, "Kami sudah biasa bepergian
dan berdagang dengan bebas."
Takeo berkata, "Mungkin kelak hal itu
bisa dilakukan. Kami tahu bahwa Anda bisa
membayar dengan mata uang perak, tapi bila
terlalu banyak mata uang perak masuk,
semua harga akan jatuh. Kami harus
melindungi rakyat, dan menjalankannya
secara perlahan. Bila perdagangan ini ter-
nyata mendatangkan keuntungan bagi kami,
maka kami akan memperluasnya."
"Dengan persyaratan seperti ini, maka
keuntungan tak berada di pihak kami,"
bantah Don Joao. "Bila itu keputusannya,
maka kami berdua akan pergi."
"Itu keputusan Anda," Takeo sepakat
dengan sopan, sadar kalau hal itu sulit
diterima.
Lalu Don Carlo mengungkit masalah
agama, dan bertanya apakah mereka boleh
membangun kuil di Hofu dan di Hagi, dan
apakah penduduk setempat boleh bergabung
dengan mereka memuja Deus.
"Rakyat kami boleh beribadah sesuai
keinginan mereka," sahut Takeo. "Tidak
perlu membuat bangunan khusus untuk itu.
Kami akan memberi akomodasi. Anda boleh
memanfaatkan satu ruangan di sana. Tapi,
saranku, jangan secara terang-terangan.
Prasangka masih tetap ada, jangan sampai
menganggu keselarasan dalam masyarakat."
"Kami berharap Lord Otori bisa mengakui
agama kami sebagai salah satu agama yang
benar," tutur Don Carlo, dan Takeo mcngira
kalau ia menangkap nada lebih bersemangat
Madaren sewaktu menerjemahkan.
Takeo tersenyum, seolah gagasan itu
terlalu absurd untuk dibicarakan. "Takkan
ada hal semacam itu," sahutnya, dan melihat
kalau hal itu membuat mereka kesal.
"Anda berdua harus kembali ke Hofu,"
ujarnya, seraya berpikir akan menulis surat
kepada Taku. "Aku akan mengatur kapal
dengan Terada Fumiodia akan menemani
Anda. Aku akan pergi selama musim panas,
dan istriku akan sangat sibuk mengurus anak.
Tak ada alasan lagi bagi kalian untuk tinggal
di Hagi."
"Aku akan merasa kehilangan Lady
Otori," kata Don Carlo. "Lady Otori telah
menjadi murid sekaligus guru, dan hebat
dalam keduanya."
Kaede berbicara padanya menggunakan
bahasa asing itu; Takeo kagum dengan
kefasihan istrinya dalam bahasa yang aneh
bunyinya itu.
"Aku berterima kasih kepadanya dan
bilang kalau dia juga pandai sebagai murid,
serta berharap dia mau terus belajar dari
kita," tutur Kaede dengan pelan pada Takeo.
"Kukira dia lebih suka menjadi guru
ketimbang menjadi murid," bisik Takeo, tak
ingin Madaren mendengar.
"Ada banyak hal yang dia merasa sudah
tahu," sahut Kaede pelan.
"Tapi Lord Otori akan ke mana begitu
lama, begitu cepat setelah kelahiran anak
Anda?" tanya Don Joao.
Seturuh kota sudah tahu: tak ada alasan
menyembunyikannya dari mereka. "Aku
akan mengunjungi Kaisar."
Ketika diterjemahkan, mereka tampak
kebingungan. Mereka mengajukan per-
tanyaan pada Madaren dengan hati-hati,
seraya melihat sekilas ke arah Takeo dengan
tatapan terkejut.
"Apa yang mereka katakan?" Takeo men-
condongkan badan ke arah Kaede dan ber-
bicara di telinga istrinya.
"Mereka tidak tahu kalau ada Kaisar,"
gumamnya. "Mereka mengira kalau kaulah
yang mereka sebut raja."
"Dari Delapan Pulau?"
"Mereka tidak tahu tentang Delapan
Pulaumereka mengira hanya ada Tiga
Negara."
Madaren bicara dengan ragu-ragu,
"Maafkan aku, tapi mereka ingin tahu
apakah mereka boleh menemani Lord Otori
ke ibukota."
"Apa mereka sudah gila?" imbuhnya cepat,
"Jangan terjemahkan itu! Katakan pada
mereka kalau masalah ini telah dipersiapkan
berbulan-bulan sebelumnya. Hal itu tidak
mungkin."
Don Joao memaksa. "Kami adalah utusan
raja kami. Sudah sepantasnya kami diper-
bolehkan memperlihatkan surat kepercayaan
raja kami pada penguasa negeri ini, bila
memang bukan Lord Otori orangnya."
Don Carlo lebih diplomatis. "Mungkin
memang seharusnya kami mengirim surat
dan hadiah. Mungkin Lord Otori bisa
menjadi duta bagi kami."
"Kemungkinan itu bisa dilakukan," aku
Takeo, dalam hati ia bertekad tidak akan
melakukannya. Setelah menerima makanan
kecil dari Haruka, mereka mengucapkan
selamat tinggal, berjanji akan mengirim surat
dan hadiah sebelum Takeo pergi.
"Ingatkan pada mereka kalau hadiahnya
harus mewah dan indah," kata Takeo pada
Madaren, karena biasanya apa yang dianggap
cukup oleh orang asing jauh dari yang biasa
mereka lakukan. Takeo memikirkan dengan
gembira kesan yang akan dibuat oleh kirin.
Kaede sudah memerintahkan dipersiapkan-
nya kain sutra yang indah, dan dikemas
dengan bungkusan kertas halus bersama
contoh keramik terindah, kotak penyimpan
teh dari emas dan pernis hitam, serta lukisan
pemandangan karya Sesshu; Shigeko akan
membawa kuda-kuda dari Maruyama dan
gulungan kaligrafi terbuat dari daun emas,
ketel besi dan rak lentera. Semua itu untuk
menghormati Kaisar dan memperlihatkan
kekayaan dan status kedudukan Klan Otori
serta kekayaan negaranya. Takeo sangsi
benda apa pun yang bisa disediakan kedua
orang asing itu bisa layak dibawa sampai ke
ibukota, bahkan untuk diberikan kepada
menteri sekali pun.
Takeo sudah melangkah keluar menuju
taman sewaktu kedua orang asing itu
mengundurkan diri, seraya membungkuk
dengan sikap mereka yang canggung dan
kaku. Ketimbang mengantar mereka sampai
ke gerbang, Madaren justru berlari mengejar.
Tindakan adiknya membuat ia gusar karena
tidak ingin didekati, namun ia pun sadar
kalau Madaren sudah akrab dengan istrinya
selama musim dingin. Kebalikan dari
sikapnya, ia merasa ada semacam kewajiban
pada Madaren; menyesali sikapnya yang
dingin. Untungnya, bila ada yang melihat
mereka bersama, mereka akan mengira
perempuan itu bicara padanya sebagai
penerjemah, bukan kerabatnya.
Madaren memanggil namanya; Takeo
berbalik, dan saat Madaren tidak sanggup
bicara, dia berkata dengan ramah, "Apa yang
bisa kubantu? Adakah kebutuhanmu yang
belum terpenuhi? Apakah kau perlu uang?"
Madaren menggelengkan kepala.
"Apa sebaiknya kuaturkan pernikahan
untukmu? Aku akan mencarikan pedagang
yang cocok denganmu. Kau bisa memulai
usahamu sendiri, dan juga keluargamu."
"Aku tidak ingin semua itu," sahutnya.
"Don Joao membutuhkan diriku. Aku tidak
bisa meninggalkannya."
Takeo mengira kalau adiknya ingin ber-
terima kasih, dan terkejut ketika temyata
bukan itu yang dikatakannya. Sebaliknya, dia
malah bicara dengan nada agak keras. "Ada
satu hal yang kuinginkan lebih dari segala-
nya. Dan itu hanya kau yang bisa berikan."
Takeo menaikkan alis dan menanti
kelanjutan kata-kata adiknya.
"Tomasu," katanya dengan berlinang air
mata. "Aku tahu kau belum sepenuhnya ber-
paling dari Tuhan. Katakan padaku kalau
kau masih menjadi pengikut Hidden."
"Aku tidak lagi pengikut ajaran itu,"
sahutnya tenang. "Maksudku, seperti yang
tadi kukatakan: tak ada satu agama pun yang
benar."
"Saat kau mengeluarkan kata-kata tak
pantas itu, Tuhan mengirimkan firasat
kepadaku." Air mata berlinang di wajahnya.
Rasa tertekan dan ketulusannya tak dira-
gukan lagi. "Aku melihatmu terbakar di
neraka. Api neraka melahap dirimu. Itulah
yang menantimu setelah kematian, kecuali
kau kembali kepada Tuhan."
Takeo ingat pesan dari tuhan yang
mendatangi dirinya setelah demam karena
terkena racun yang membawa dirinya ke
ambang alam baka. Ia takkan percaya pada
kepercayaan mana pun, agar rakyatnya bebas
memilih. Pendiriannya tidak akan goyah.
"Madaren," ujarnya lembut. "Kau tidak
boleh bicara denganku mengenai masalah ini.
Aku melarangmu mendekatiku dengan cara
seperti ini lagi."
"Tapi kehidupan kekalmu menjadi
taruhannya; jiwamu. Sudah menjadi tugasku
untuk menyelamatkan dirimu. Kau pikir
mudah bagiku untuk melakukannya? Lihat
betapa gemetarnya tubuhku! Aku takut
mengutarakan kata-kata ini padamu. Tapi
aku harus mengatakannya!"
"Hidupku di sini, di dunia ini," sahutnya.
Takeo memberi isyarat agar adiknya melihat
ke taman, dalam segala keindahannya di
musim semi. "Tidakkah ini cukup? Dunia
tempat kita lahir dan tempat kita mati;
tempat kembalinya jiwa dan raga dalam
siklus besar, siklus kehidupan dan kematian?
Ini sudah cukup indah dan menakjubkan."
"Tapi Tuhan yang menciptakan dunia
ini," katanya.
"Tidak, dunia menciptakan dirinya
sendiri; jauh lebih hebat dari yang kau kira."
"Tidak mungkin lebih hebat dibanding
Tuhan."
"Tuhan, dewa, semua itu diciptakan oleh
manusia," tuturnya, "jauh lebih kecil
ketimbang dunia yang kita diami ini." Ia
tidak marah lagi, tapi tidak bisa melihat ada
alasan mengapa dia tertahan di tempat itu
oleh adiknya itu, meneruskan perbincangan
yang tak ada tujuannya.
"Kedua majikanmu sedang menunggu.
Sebaiknya kau kembali pada mereka. Dan
kularang kau mengungkapkan masa laluku
pada mereka. Kuharap kau sadar sekarang
kalau masa lalu sudah ditutup rapat. Aku
telah memutus tali hubungannya. Keadaanku
saat ini membuatku mustahil untuk kembali.
Kau akan selalu menikmati perlindunganku,
tapi bukannya tanpa syarat."
Ia merasa kedinginan, padahal cuaca hari
itu hangat. Apa maksud perkataannya; apa
yang akan ia lakukan pada adiknya itu?
Mengeksekusinya? Diingatnya, seperti yang
diingatnya setiap hari, kematian Jo-An di
tangannya, gelandangan yang juga meng-
anggap dirinya sebagai utusan Tuhan
Rahasia. Tak peduli seberapa dalam
penyesalan atas lindakannya itu, ia sadar
kalau ia bisa melakukannya lagi tanpa ragu.
Ia telah membunuh masa lalunya, keyakinan
masa kecilnya dengan Jo-An, dan tak satu
pun dari mereka bisa dibangkitkan kembali.
Madaren tunduk pada kata-katanya. "Lord
Otori," dia membungkuk hormat sampai ke
tanah, seolah sadar tempatnya yang
sebenarnya, bukan sebagai adiknya tapi
serendah pelayanseperti Haruka yang
menunggu setengah bersembunyi di beranda.
"Semuanya baik-baik saja, Lord Takeo?"
"Juru bahasa itu mengajukan beberapa
pertanyaan," sahutnya. "Lalu kelihatannya
dia kurang sehat. Pastikan perempuan itu
pulih kembali, dan pastikan kalau dia pergi
secepatnya."*
Terada Fumio menghabiskan musim dingin
di Hagi bersama istri dan anak-anaknya. Tak
lama setelah pertemuan dengan orang asing
selesai, Takeo pergi ke rumah mereka yang
berida di sisi lain teluk. Taman beratap,
dihangatkan dengan sumber air panas yang
mengelilingi gunung berapi, kelihatan cerah
dengan azalea dan peony beserta tumbuhan
eksotis lainnya yang dibawa Fumio untuk
Eriko dari pulau-pulau yang jauh serta
kekaisaran-kekaisaran terpencil: anggrek, lili
dan mawar.
"Suatu hari nanti kau harus ikut dengan-
ku," kata Fumio selagi mereka berjalan
melewati taman dan menceritakan tempat
asal tiap tumbuhan. "Kau belum pernah
keluar Tiga Negara."
"Tidak perlu, karena kau sudah mem-
bawakan dunia kepadaku." sahut Takeo.
"Tapi kelak aku ingin ikutjika aku
mengundurkan diri atau turun takhta."
"Apa kau memang mempertimbangkan
hal itu?" Fumio mengamati, tatapan matanya
yang penuh semangat menelusuri wajah
Takeo.
"Lihat saja nanti apa yang akan terjadi di
Miyako. Aku berharap bisa memecahkan
masalah tanpa berperang. Saga Hideki
mengusulkan suatu penandinganputriku
yang akan menggantikan dirikudan yang
lainnya sudah yakin kalau hasilnya kelak
akan berpihak kepadaku."
"Kau mempertaruhkan Tiga Negara hanya
dalam satu penandingan? Jauh lebih baik ber-
siap untuk berperang!"
"Seperti yang kita putuskan tahun lalu,
kita akan siap perang. Setidaknya aku butuh
waktu satu bulan hingga sampai di ibukota.
Selama itu Kahei akan mengumpulkan
pasukan di perbatasan wilayah Timur. Aku
diwajibkan ikut penandingan itu, menang
atau kalah, tapi dengan syarat yang akan
dibicarakan dengan Saga. Kekuatan kita akan
berada di sana hanya jika syaratku tidak
dipenuhi, atau jika mereka ingkar janji."
"Kita harus menggerakkan armada dari
Hagi ke Hofu," tutur Fumio. "Itu berarti
kita mengendalikan bagian Barat dari laut,
dan bisa menyerang di Kumamoto bila
perlu."
"Bahaya terbesar yaitu Zenko memanfaat-
kan ketidak-hadiranku dan memberontak.
Tapi istrinya akan ke Hagi; kedua putranya
sudah berada di sana. Menurutku, dia tak
akan benindak bodoh dengan mempertaruh-
kan nyawa mereka. Kaede sepakat denganku,
dan dia akan mengupayakan seluruh
pengaruhnya atas Hana. Kau dan ayahmu
harus pergi dengan armada perang ke Hofu;
bersiap menerima serangan dari laut. Taku
ada di sana dan akan tetap memberitahukan
padamu apa pun yang terjadi. Dan kau bisa
mengajak orang-orang asing itu bersamamu."
"Mereka akan kembali ke Hofu?"
"Mereka akan membangun pos dagang di
sana. Kau bantu mereka melakukannya
sambil mengawasi. Gadis Muto itu, Mai,
juga akan pergi bersama mereka."
Takeo terus menceritakan tentang
kekhawatirannya atas orang-orang a,sing
karena kemungkinan sudah ada yang tinggal
di Kumamoto.
"Aku akan mencari tahu semampuku,"
Fumio berjanji. "Aku harus mengenal Don
Joao dengan cukup baik musim dingin ini,
dan mulai mengerti bahasa mereka. Untung-
nya dia bukan orang yang tertutup, terutama
setelah minum sake. Bicara tentang sake,"
imbuhnya. "Mari kita minum beberapa
cangkir. Ayahku ingin bertemu denganmu."
***
Ia lupa pada semua kecemasannya saat
menikmati sake dan makanan yang disiapkan
Eriko, ikan segar dan sayuran musim semi,
ditemani kawannya si perompak tua
Fumifusa, serta taman yang indah.
Takeo pulang ke rumah melalui tepi
sungai, masih dengan pikiran yang tenang
dan ceria. Saat memasuki taman, semangat-
nya bangkit lagi ketika mendengar suara
Shizuka.
"Kau tidak ajak Miki?" tanyanya saat ber-
gabung dengan Shizuka di ruangan atas;
Haruka menyajikan teh lalu meninggalkan
mereka berdua.
"Pikirannya bercabang tentang masalah
itu," sahut Shizuka. "Dia ingin bertemu
denganmu. Dia merindukanmu, juga kakak-
nya. Tapi dia kini dalam usia ketika dapat
menyerap semua pelajaran dengan cepat.
Sepertinya tidak bijaksana kalau tidak
dimanfaatkan. Dan karena kau akan pergi
selama musim panas ini, serta Kaede akan
sibuk dengan bayinya...."
"Aku sebenarnya berharap bisa bertemu
dengannya sebelum pergi," sahut Takeo.
"Dia sehat-sehat saja?"
Shizuka tersenyum. Tumbuh dengan baik.
"Dia mengingatkanku pada Yuki saat
seusianya. Penuh percaya diri. Dia ber-
kembang tanpa kehadiran Maya, bahkan
ternyata sangat baik baginya keluar dari
bayang-bayang kakaknya."
Mendengar nama Yuki disebut membuat
Takeo hanyut dalam lamunan. Menyadari
itu, Shizuka berkata, "Aku dapat kabar dari
Taku pada akhir musim dingin. Dia bilang
Akio berada di Kumamoto bersama dengan
putramu."
"Benar. Aku tak ingin membicarakannya
di sini, tapi kehadirannya di tempat Zenko
berdampak pada banyak hal yang harus
kubicarakan denganmu. Apakah para tetua
Muto mendukungmu?"
"Ada perbedaan pendapat," sahut Shizuka.
"Bukan di Negara Tengah, tapi dari wilayah
Timur dan Barat. Aku terkejut Taku belum
kembali ke Inuyama, tempat dia bisa
mengerahkan kendali atas kaum Tribe di
wilayah Timur. Aku harus ke sana, tapi aku
enggan meninggalkan Kaede di saat seperti
ini, apalagi kau akan segera berangkai."
"Taku sudah terobsesi pada gadis yang
kami kirim untuk merawat Maya," ujar
Takeo, merasakan percikan kemarahan yang
sama.
"Kudengar desas-desus tentang itu. Aku
khawatir bila kedua putraku membuatmu
kecewa, setelah semua yang kau lakukan
demi mereka."
Suaranya kedengaran teratur, tapi Takeo
melihat kalau Shizuka benar-benar tertekan.
"Aku percaya pada Taku," ujar Takeo.
"Tapi gangguan semacam itu hanya akan
membuatnya gegabah. Zenko lain lagi
masalahnya, tapi untuk sementara ini dia
masih bisa dikendalikan. Tampaknya dia
bertekad untuk menuntut jabatan ketua
Muto, dan itu akan menjadi konflik dengan
dirimu, dan Taku serta tentu saja aku.'
Takeo berhenti sejenak, lalu berkata, "Aku
sudah berusaha meredamnya; mengancam
dan memberi perintah padanya, tapi dia
tetap ingin memancing amarahku."
Shizuka berkata, "Dia semakin mirip
dengan ayahnya. Aku tak bisa lupa kalau Arai
memerintahkan kematianku, dan sanggup
menyaksikan kau membunuh putranya
sendiri, demi kekuasaan. Saranku, sebagai
pemimpin keluarga Muto sekaligus sahabat
keluarga Otori, yaitu secepatnya menyingkir-
kan Zenko, sebelum dia mengumpulkan
lebih banyak dukungan lagi. Aku yang akan
mengaturnya. Kau hanya perlu memberi
perintah."
Mata Shizuka berkilat, tapi tidak ada air
mata.
"Hari pertama kita bertemu, Kenji berkata
kalau aku harus belajar kekejaman dari
dirimu," sahut Takeo, kagum karena Shizuka
bisa dengan sikap dingin menyarankan untuk
membunuh putra sulungnya sendiri.
"Tapi Kenji dan aku tak sanggup
menanamkan sifat itu ke dalam dirimu,
Takeo. Zenko tahu itu, itu sebabnya dia
tidak takut atau hormat padamu."
Kata-kata Shizuka menyengat dirinya,
namun ia menjawab dengan ringan, "Aku
sudah berjanji pada diriku dan pada negara
ini untuk mengambil jalan perundingan
demi mencapai keadilan serta kedamaian.
Aku tak membiarkan tantangan Zenko
mengingkari janji itu."
"Maka tangkap dan adili dia dengan
tuduhan makar. Buatlah sah menurut
hukum, tapi bertindaklah cepat." Shizuka
mengamati, dan saat tidak ada jawaban, dia
meneruskan, "Tapi kau takkan mengikuti
saranku, Takeo; kau tidak perlu mengatakan
apa-apa. Tentu saja, aku berterima kasih
padamu karena membiarkan putraku tetap
hidup, tapi akibat yang harus ditanggung kita
semua tak terbayangkan besarnya."
Ucapan Shizuka membuat sapuan dingin
firasat merayap hingga ke tulang punggung-
nya. Matahari telah tenggelam dan taman
berganti dengan cahaya biru malam.
Kunang-kunang berkelap-kelip di atas aliran
sungai, dan dilihatnya Sunaomi dan Chikara
datang sambil mencipakkan air di bawah
dindingmereka pasti habis bermain di tepi
sungai. Rasa lapar yang membawa mereka
pulang. Bagaimana Takeo bisa membunuh
ayah mereka? Ia justru hanya akan membuat
kedua bocah itu bersikap menentangnya dan
keluarganya, lalu memperpanjang pertikaian.
"Aku menawarkan Miki untuk ditunang-
kan dengan Sunaomi," komentar Takeo.
"Tindakan yang sangat bagus." Shizuka
tampak berusaha agar suaranya kedengaran
lebih ringan, "Walaupun kupikir tak satu
pun dari keduanya akan berterima kasih
padamu! Jangan katakan ini pada siapa pun;
Sunaomi pasti membenci usulan ini. Dia
sangat kesal dengan kejadian di musim panas
kemarin itu. Kelak saat sudah dewasa baru
dia bisa menyadari betapa besar kehormatan
yang diterimanya."
"Masih terlalu dini untuk mengumum-
kannyamungkin setelah aku kembali pada
akhir musim panas."
Dari ekspresi Shizuka, dia seakan mem-
peringatkan kalau ia takkan punya negara
lagi yang bisa dipulanginya, tapi pembicaraan
mereka disela oleh teriakan dari belakang
rumah, tempat para perempuan. Takeo
mendengar langkah Haruka berlari di
beranda, membuat nightingale floor ber-
nyanyi.
Di taman kedua bocah berdiri dan
menatap Haruka.
"Shizuka, Tabib Ishida," teriak Haruka.
"Cepat kemari! Lady Otori sudah mau
melahirkan."
***
Bayi itu, seperti keinginan Kaede selama ini,
berjenis kelamin laki-laki. Kabar itu langsung
dirayakan di seluruh kota Hagi, meski dalam
batasan tertentu karena cengkeraman si bayi
pada tangan kehidupan masih lemah serta
rapuh. Proses kelahiran berlangsung cepat,
bayinya kuat dan sehat. Tampaknya jelas
kalau Lady Otori akan memiliki seorang
putra sebagai pewaris. Kutukan yang dibisik-
kan rakyat yang karena kelahiran si kembar
telah sirna.
Kabar itu diterima dengan kegembiraan
yang sama selama beberapa minggu
kemudian di seluruh penjuru Tiga Negara,
setidaknya di Maruyama, Inuyama dan
Hofu. Kemungkinan kegembiraan itu kurang
dirasakan di Kumamoto, tapi Zenko dan
Hana mengirimkan hadiah yang indah:
jubah sutra untuk si bayi, pedang kecil milik
keluarga Arai, dan seekor kuda poni. Hana
bersiap melakukan perjalanan ke Hagi di
akhir musim panas, bersemangat untuk
bertemu dengan kedua putra kandungnya
dan menemani kakaknya sementara Takeo
pergi.
Ketika masa pingitan Kaede berakhir, dan
kediaman telah disucikan sesuai adat, Kaede
membawa si bayi dan menaruh si bayi di
gendongan sang ayah.
"Ini yang kudambakan seumur hidupku,"
tutur Kaede. "Memberimu seorang putra."
"Kau sudah memberiku lebih dari yang
kuharapkan," sahutnya dengan penuh
perasaan. Takeo belum siap untuk menerima
makhluk mungil berwajah merah dan
berambut hitam inidan untuk kebanggaan
dalam dirinya. Menggendong putranya
sendiri membuat ia merasa berbeda. Sudut
matanya mulai terasa hangat, namun ia tak
bisa berhenti tersenyum.
"Kau bahagia!" seru Kaede. "Aku takut...
begitu sering kau mengatakan tidak meng-
inginkan anak laki-laki, bahwa kau bahagia
dengan ketiga putri kita, hingga aku hampir
saja memercayaimu."
"Aku memang bahagia," sahutnya. "Aku
bisa mati saat ini juga."
"Aku merasakan hal yang sama," gumam
Kaede. "Tapi jangan bicara tentang
kematian. Kita akan hidup untuk melihat
putra kita dewasa."
"Aku berharap tidak meninggalkanmu."
Seketika ia terpukau pada pikiran untuk
mengabaikan perjalanan ke Miyako. Biar saja
Si Pemburu Anjing menyerang; pasukan
Tiga Negara akan menghabisinya dengan
mudah, dan kemudian menghadapi Zenko.
Ia tercengang dengan kekuatan perasaan itu;
ia akan bertempur sampai titik darah
penghabisan untuk mempertahankan Tiga
Negara agar bayi ini bisa mewarisinya.
Dipertimbangkannya masak-masak hal itu,
lalu ia singkirkan dari benaknya. Ia akan
mencoba cara damai dulu, seperti yang telah
diputuskan; jika perjalanan itu ditunda,
maka ia akan terlihat arogan sekaligus
pengecut.
"Aku juga berharap demikian," sahut
Kaede. "Tapi kau harus pergi." Diambilnya si
bayi lalu menatap wajah bayi mungil itu,
wajah Kaede penuh kasih sayang. "Aku tidak
akan sendirian lagi dengan laki-laki mungil
ini di sisiku!"
Takeo harus pergi sesegera mungkin agar bisa
sampai di tujuan sebelum mulai hujan plum.
Shigeko dan Hiroshi tiba dari Maruyama,
dan Miyoshi Gemba dari Terayama. Miyoshi
Kahei sudah berangkat ke wilayah Timur tak
lama setelah salju mencair. Dia membawa
kekuatan utama pasukan Otori: lima belas
ribu pasukan dari Hagi dan Yamagata;
sepuluh ribu orang lagi akan dihimpun
Sonoda Mitsuru di Inuyama, Sejak musim
panas, beras dan gandum, ikan kering serta
miso telah disimpan sebagai cadangan dan
disebar sampai ke perbatasan wilayah Timur
untuk persediaan bagi pasukan. Beruntung
panen kali ini berlimpah: baik pasukan
maupun mereka yang penduduk takkan
kelaparan.
Dalam mengatur perjalanan, yang paling
membebani yaitu kirin. Hewan itu kini lebih
tinggi, dan kulitnya menjadi lebih gelap
seperti warna madu, tapi ketenangan dan
kedamaiannya tak berubah. Menurut Tabib
Ishida, hewan itu sebaiknya tidak ikut
berjalan kaki ke sana karena Jajaran Awan
Tinggi akan terlalu berat baginya.
Pada akhimya diputuskan kalau Shigeko
dan Hiroshi yang akan membawanya dengan
kapal sampai di Akashi.
"Kita semua bisa menumpang kapal,
Ayah," Shigeko menyarankan.
"Ayah belum pernah keluar perbatasan
Tiga Negara," sahut Takeo. "Ayah ingin
melihat daratan dan jalan melewati jajaran
itu; bila ada badai di bulan kedelapan dan
kesembilan, maka laut adalah jalan yang akan
kita lalui untuk kembali. Fumio akan ke
Hofu: dia akan membawamu dan kirin,
begitu pula dengan orang-orang asing itu."
Bunga ceri berguguran dan kelopaknya
berganti daun hijau yang baru ketika Takeo
dan rombongannya berkuda dari Hagi,
melewati pegunungan dan jalan pantai
menuju Matsue. Takeo pernah melewati
jalur bersama Lord Shigeru. Jalur ini
mengembalikan kenangan pada orang yang
telah menyelamatkan dan mengangkatnya
sebagai anak.
Aku bilang kalau tidak memercayai apa
pun, pikirnya, tapi aku sering mendoakan
arwah Shigeru; terutama saat sekarang ini,
ketika aku membutuhkan kearifan serta
keberaniannya. Padi mulai tumbuh di sawah
yang tergenang, memantulkan kilau me-
mesona saat disirami cahaya matahari. Di
tepiannya, di mana ada persimpangan jalan,
berdiri sebuah kuil kecil; dilihatnya kalau
kuil itu dipersembahkan bagi Jo-An, yang di
beberapa tempat telah dianggap dewa.
Alangkah anehnya kepercayaan orang-orang
itu, pikirnya sambil mengenang percakapan-
nya dengan Madaren beberapa minggu lalu:
keyakinan yang memaksa adiknya bicara
padanya. Keyakinan yang sama ditunjukkan
oleh Jo-Andan kini Jo-An telah menjadi
orang suci.
Ia melihat sekilas pada Miyoshi Gemba
yang berkuda di sampingnya, teman seper-
jalanan yang paling tenang dan paling ceria
yang bisa diharapkan. Gemba telah meng-
ikuti Ajaran Houou; ajaran yang penuh
pengendalian diri. Saat berkuda, Gemba
acapkali tenggelam dalam meditasi, dan
sesekali bersenandung pelan, bak suara
halilintar dari kejauhan atau raungan
beruang. Ia membicarakan tentang Sunaomi,
yang pernah bertemu Gemba di Terayama,
menceritakan tentang rencananya untuk
menjodohkan bocah itu dengan putrinya.
"Dia akan menjadi menantuku. Itu akan
memuaskan ayahnya!"
"Kecuali Sunaomi memiliki perasan
sebagai putra yang berbakti padamu, maka
pertunangan itu takkan berguna," sahut
Gemba.
Takeo terdiam, teringat kejadian di biara,
perselisihan antarsepupu, takut kalau
Sunaomi terluka atas kejadian itu.
"Dia melihat burung houou," akhirnya ia
berkata. "Aku percaya kalau anak itu punya
naluri yang baik."
"Ya, aku juga berpikir begitu. Baiklah,
kirim anak itu pada kami. Kami akan
merawatnya, dan bila ada kebaikan dalam
dirinya, maka akan dipupuk dan dikembang-
kan."
"Kurasa usianya sudah cukup dewasa:
tahun ini usianya sembilan tahun."
"Ijinkan dia ke tempat kami saat kita
kembali."
"Dia tinggal bersamaku sebagai ke-
ponakanku, sebagai calon putraku, namun
juga sebagai sandera atas kesetiaan ayahnya.
Aku takut kelak terpaksa memerintahkan
untuk membunuhnya," aku Takeo.
"Hal itu tidak akan terjadi," kata Gemba.
"Aku akan menyurati istriku nanti malam
tentang usulanmu itu."
Minoru mendampinginya seperti biasa,
dan malam itu di pemberhentian pertama
mereka, ia mendiktekan surat untuk Kaede,
dan untuk Taku di Hofu. Ia merasa perlu
bicara dengan Taku; mendengar kabar
terbaru dari wilayah Barat, serta memintanya
datang ke Inuyama agar bisa bertemu di sana.
Bagi Taku, perjalanan itu mudah karena
melalui laut dari Hofu, kemudian melalui
sungai dengan menumpang kapal tongkang
yang melintasi antara kota kastil dengan
pesisir.
"Datanglah sendiri," diktenya. "Jinggalkan
tanggunganmu dan pendampingnya di Hofu.
Bila tidak dapat melepaskan diri, kabari aku."
"Apakah ini bijaksana?" tanya Minoru.
"Surat bisa saja dikacaukan, terutama...."
"Terutama apa?"
"Bila keluarga Muto tidak lagi yakin
kepada siapa mereka akan berpihak?"
Karena Takeo mengandalkan Tribe untuk
membawa pesan tertulis dengan cepat ke
seluruh Tiga Negara. Itulah yang ia harapkan
dapat dikendalikan Taku.
Ia menatap Minoru, keraguan mulai
merayapi dirinya. Jurutulisnya tahu lebih
banyak rahasia Tiga Negara dibanding siapa
pun.
"Bila keluarga Muto memilih Zenko,
mana yang akan Taku pilih?" katanya pelan.
Minoru menaikkan bahu, tapi bibimya
terkatup rapat dan tidak langsung menjawab.
"Perlu kutuliskan kalimat terakhir Anda?" dia
bertanya.
"Tekankan kalau Taku harus datang
sendiri."
Percakapan ini melekat di benak Takeo
sewaktu mereka melanjutkan perjalanan ke
wilayah Timur. Aku telah memperdaya Kikuta
begitu lama, pikirnya. Dapatkah aku lolos dari
Muto juga, bila mereka berbalik menentangku?
Takeo mulai mencurigai kesetiaan Kuroda
bersaudara, Jun dan Shin, yang selalu men-
dampinginya. Ia selalu memercayai mereka
sampai saat ini: meski mereka tidak memiliki
kemampuan menghilang, namun mereka
bisa merasakannya, dan mereka telah dilatih
teknik bertarung cara Tribe oleh Kenji.
Mereka telah berulang kali melindunginya,
tapi bila mereka harus memilih antara dirinya
dan Tribe, Takeo bertanya pada dirinya
sendiri lagi, jalan mana yang akan mereka
ambil?
Takeo tetap bersikap siaga, senantiasa
mendengarkan suara terpelan yang bisa jadi
pertanda satu serangan. Kudanya, Tenba,
menangkap suasana hari penunggangnya;
sudah beberapa bulan ini Takeo
menungganginya, hingga terjalin ikatan kuat
antara mereka, hampir sama kuatnya dengan
Shun; Tenba cepat tanggap dan pintar, tapi
jauh lebih tegang. Penunggang dan kuda,
keduanya tiba di Inuyama dalam keadaan
tegang serta kelelahan, sementara bagian
terberat dalam perjalanan itu masih belum
tiba.
Inuyama dipenuhi dengan kegembiraan
dan sibuk; kedatangan Lord Otori dan
penghimpunan pasukan berarti pedagang
dan pembuat senjata sibuk siang dan malam;
uang dan sake mengalir sama derasnya.
Takeo disambut adik iparnya, Ai, dan
suaminya Sonoda Mitsuru.
Takeo menyayangi Ai, kagum akan sifat
lembut dan kebaikan hatinya. Dia tidak
secantik kedua saudaranya, namun
penampilannya menarik. Satu hal yang mem-
buat Takeo senang yaitu Ai dan Mitsuru
menikah atas dasar cinta. Ai kerap men-
ceritakan tentang bagaimana penjaga di
Inuyama hampir membunuh dia dan Hana
ketika mendengar kabar kematian Arai dan
kehancuran pasukannya. Beruntung Mitsuru
telah lebih dulu mengambil alih kastil,
menyembunyikan kedua gadis itu, lalu
merundingkan penyerahan wilayah Timur
pada Otori. Karena rasa terima kasih itulah
maka Takeo menikahkannya dengan Ai,
yang memang saling mencintai.
Takeo memercayai kedua orang ini;
mereka terikat oleh hubungan perkawinan,
dan Mitsuru telah menjadi orang yang
pragmatis, sensitif tanpa berkurangnya
keberaniannya. Seringkali dia berhasil meng-
gunakan keahlian berundingnya untuk
mewakili Takeo: bersama istrinya, dia ber-
bagi angan Takeo akan negara yang makmur
tanpa penyiksaan maupun suap.
Namun rasa lelah membuat Takeo men-
curigai semua orang di sekelilingnya. Sonoda
berasal dari Klan Arai, ia memperingatkan
dirinya sendiri. Pamannya, Akita, dulu adalah
orang kepercayaan Arai. Seberapa besar sisa
kesetiaan ada dalam dirinya ter-hadap putra
Arai?
Takeo semakin gelisah dengan kenyataan
tidak adanya tanda-tanda keberadaan Taku,
ataupun kabarnya. Dipanggilnya istri Taku,
Tomiko; yang mendapatkan surat dari
suaminya saat musim semi, tapi akhir-akhir
ini belum ada kabar. Tomiko tidak terlihat
khawatir, lagipula; dia sudah terbiasa dengan
ketidakhadiran suaminya.
"Apabila ada masalah. Lord Otori, maka
kita akan segera mendengar kabarnya. Ber-
bagai urusan pasti menahannya di Hofu
mungkin sesuatu yang tak ingin dia tulis
dalam surat."
Tomiko melihat sekilas ke arah Takeo lalu
berkata, "Aku sudah dengar tentang
perempuan itu, tentunya, tapi aku sudah
menduga hal semacam itu. Semua laki-laki
punya kebutuhan, dan suamiku berada jauh
dalam waktu lama. Itu bukanlah hal yang
serius. Suamiku tidak pernah serius tentang
hal itu."
Kekhawatiran Takeo justru kian ber-
tambah saat ia mendengar kalau para sandera
yang seharusnya telah dieksekusi ternyata
masih hidup.
"Aku sudah kirim suratnya beberapa
minggu lalu, memerintahkan agar dilakukan
secepatnya."
"Maaf, Lord Otori: kami tidak me-
nerima" Sonoda mulai angkat bicara, tapi
Takeo memotong perkataannya.
"Tidak menerima atau mengabaikan?"
Takeo sadar kalau cara bicaranya terlalu blak-
blakan. Sonoda berusaha keras menyem-
bunyikan rasa tersinggungnya.
"Kuyakinkan kepada Anda," ujar Sonoda,
"Bila kami menerima perintah itu, kami pasti
sudah melaksanakannya. Aku pun bertanya-
tanya mengapa masalah ini ditunda begitu
lama. Aku pasti akan melakukannya sendiri,
tapi istriku selalu berpihak kepada belas
kasihan."
"Mereka kelihatan masih begitu muda,"
kata Ai. "Dan gadis itu...."
"Tadinya aku berharap mereka tetap
hidup," sahut Takeo. "Jika keluarga mereka
mau berunding, mereka tidak harus mati.
Tapi mereka tidak bereaksi apa-apa, serta
tidak memberi kabar. Menundanya lebih
lama akan dianggap sebagai kelemahan."
"Akan kuatur agar dilakukan besok,"
Sonoda meyakinkan.
"Ya, harus segera," Ai setuju. "Kau akan
hadir?"
"Karena aku sudah di sini, maka aku harus
hadir," sahut Takeo, karena ia sendiri yang
membuat aturan bahwa eksekusi untuk
pengkhinatan harus disaksikan orang yang
jabatannya paling tinggi, dirinya sendiri atau
salah seorang keluarganya atau pengawal
senior. Takeo merasa kalau peraturan itu
menekankan perbedaan hukum antara
eksekusi dan pembunuhan. Menurutnya,
pemandangan semacam itu memuakkan
sehingga ia berharap dengan menyaksikan itu
akan mencegah dirinya dari mengeluarkan
perintah dengan sembarangan.
Eksekusi dengan menggunakan pedang di-
laksanakan keesokan harinya. Ketika mereka
dibawa menghadap sebelum mata mereka
ditutupi, Takeo mengatakan bahwa ayah
mereka, Gosaburo, sudah dieksekusi Kikuta
karena ingin merundingkan nyawa mereka.
Tak satu pun dari mereka bereaksi; mungkin
mereka tidak percaya. Tampak kilatan air
mata dari mata gadis itu; selain itu, kedua
orang itu menghadapi kematian dengan
berani, bahkan bersikap menantang. Takeo
kagum dengan keberanian mereka dan
menyesali hidup mereka yang singkat, ber-
pikir dengan pedih bahwa mereka masih ada
kerabatnya, bahwa ia telah mengenal mereka
sejak kecil.
Keputusan itu dibuat bersama Kaede, dan
atas saran para pengawal seniornya.
Keputusan yang berdasarkan hukum.
Namun Takeo tetap berharap bisa melaku-
kan yang sebaliknya, dan kematian tampak
seperti pertanda buruk. *
Sepanjang musim dingin, Hana dan Zenko
sering bertemu Kuroda Yasu untuk mem-
bicarakan tentang pembukaan perdagangan
dengan orang asing, dan mereka senang
ketika Yasu mendengar Don Joao dan Don
Carlo ke Hofu pada akhir bulan. Mereka
kurang senang dengan berita bahwa Terada
Fumio telah membawa armada perang ke
perairan laut dalam dan kini mengawasi jalur
perairan.
"Katanya kapal mereka jauh lebih baik dari
kapal kita," kata Yasu. "Andai kita bisa minta
bantuan mereka!"
"Kalau mereka ingin berpihak kepada kita
menentang Otori..." ujar Hana, menyuara-
kan pikirannya.
"Mereka ingin berdagang, dan agar rakyat
mau berpindah memeluk agama mereka.
Tawarkan pada mereka salah satuatau
keduanya. Mereka akan berikan apa saja
sebagai imbalannya."
Komentar ini melekat di benak Hana
selagi bersiap-siap pergi ke Hagi. Sewaktu
memikirkan menghadapi kakaknya dengan
rahasia yang akan ia bawa, Hana merasa ber-
semangat sekaligus takut, semacam ke-
gembiraan yang menghancurkan. Tapi ia
tidak meremehkan Takeo, karena suaminya
cenderung bersikap sebaliknya. Hana
mengenal kekuatan dan karakter kakak ipar-
nya yang selalu memenangkan cinta dari
rakyatnya serta pendukung setia dari berbagai
kalangan. Mungkin juga Takeo akan me-
menangkan hati Kaisar dan kembali dengan
restu dari Kaisar. Maka Hana berpikir keras
selama musim dingin tentang strategi lebih
lanjut untuk menopang perjuangan suaminya
demi balas dendam dan kekuasaan. Saat
mendengar orang-orang asing itu sudah
kembali bersama jurubahasanya, Hana
bertekad untuk pergi ke Hagi melalui Hofu.
"Kau seharusnya ikut bersama kami," ujar
Hana pada Akio yang sudah menjadi tamu
tetap ke kastil selama musim dingin. Akio
selalu melaporkan kabar dari seluruh penjuru
negara, serta perkembangan yang tengah
dibuat Hisao dan Koji dalam penempaan.
Darah Hana selalu menggelegak dengan
kehadiran laki-laki itu. Menurutnya
kekejaman pragmatis laki-laki itu menarik.
Saat ini Akio melihat Hana dengan
tatapan yang penuh perhitungan seperti
biasa. "Ya, aku tidak keberatan. Tentu saja,
aku akan ajak Hisao."
Satu kali, mereka hanya berdua saja. Kala
itu cuaca masih dingindi akhir musim
semi dengan cuaca yang tak menentu
namun wangi bunga yang baru mekar
tercium dan malam terasa lebih ringan. Saat
itu Akio datang untuk menemui Zenko yang
sedang melihat latihan pasukan dan kuda.
Akio semula enggan tinggal lama, tapi Hana
memaksa dengan menawarkan sake dan
makanan. Dia melayani sendiri laki-laki itu,
membujuk serta menyanjungnya, membuat
Akio tak mungkin menolak.
Hana mengira Akio tidak mudah di-
pengaruhi sanjungan, tapi bisa dilihatnya
kalau perhatiannya membuat laki-laki itu
senang dan boleh dibilang menjadi lembut.
Hana ingin tahu bagaimana rasanya tidur
dengan orang itu; walau ia berpikir takkan
melakukannya, pikiran itu membuat ia ber-
semangat. Hana mengenakan jubah sutra
berwarna gading, dihiasi bunga ceri merah
muda dan burung bangau: motif penuh
warna yang digemarinya. Sesungguhnya
cuaca terlalu dingin untuk mengenakan
pakaian semacam itu, dan kulitnya terasa
dingin membeku, tapi ia sedang gembira: ia
masih muda, darahnya bergejolak dengan
dorongan yang sama seperti dorongan akar-
akar dari dalam bumi, tunas dari ranting.
Penuh percaya diri dengan kecantikannya, ia
memberanikan diri bertanya pada Akio,
sebagaimana yang diinginkannya sepanjang
musim dingin ini, tentang Hisao.
"Dia tidak mirip ayahnya," komentar
Hana. "Apakah dia mirip dengan ibunya?"
Saat Akio tidak segera menjawab, Hana
mendesak, "Seharusnya kau ceritakan semua-
nya padaku. Makin banyak yang bisa ku-
ungkapkan tentang dirimu pada kakakku,
maka semakin kuat akibatnya pada dirinya."
"Itu sudah bertahun-tahun silam," tutur-
nya.
"Jangan berpura-pura kalau kau sudah
melupakannya! Aku tahu bagaimana ke-
cemburuan mengukirkan kisahnya dengan
belati di hati kita."
"Ibunya adalah perempuan yang luar
biasa," Akio mulai bercerita. "Sewaktu di-
sarankan agar dia tidur dengan Takeo, aku
takut untuk menyuruhnya melakukan itu.
Meminta Yuki melakukan hal semacam
ituhal yang lazim di kalangan Tribe, dan
kebanyakan perempuan melakukan apa yang
diperintahkan, tapi Yuki merasa itu sebagai
penghinaan. Ketika dia setuju, kusadari kalau
Yuki menginginkan Takeo. Aku melihat dia
menggoda Takeo; bukan hanya sekali, tapi
berkali-kali. Aku tidak menyangka kalau
hatiku akan terasa sepedih itu, atau ke-
bencian yang begitu dalam pada Takeo. Aku
belum pemah membenci siapa pun; aku
membunuh atas perintah, bukan karena
perasaan pribadi. Takeo memiliki apa yang
paling kuinginkan, dan dia menyia-nyiakan-
nya. Dia meninggalkan Tribe. Bila Takeo
merasakan sedikit saja apa yang pernah
kurasakan, maka itu yang disebut keadilan."
Akio mendongak. "Aku tidak pernah tidur
dengannya," tuturnya. "Aku menyesali itu
lebih dari segalanya. Andai aku mampu
melakukannya, sekali saja... Tapi aku tidak
ingin menyentuhnya saat dia mengandung
anak Takeo. Dan aku memaksanya bunuh
diri. Aku harus melakukannya: karena Yuki
tidak berhenti mencintai Takeo; dia tidak
akan memaksa anak itu membenci Takeo
seperti yang telah kulakukan. Aku tahu dia
harus menjadi bagian dari balas dendamku,
tapi seiring tumbuh dewasa, dia tidak
menunjukkan bakat apa pun, aku tidak tahu
mengapa. Dalam waktu yang lama kukira
memang tidak ada harapan lagi: berulang
kali, para pembunuh yang jauh lebih
terampil dari Hisao saja gagal. Kini kutahu
kalau Hisao yang akan mcmbalaskan
dendamku. Dan aku akan ada di sana untuk
menyaksikannya." Mendadak Akio berhenti
bicara.
Kata-kata itu meluncur deras dari mulut-
nya. Dia telah menyimpan semua ini rapat-
rapat selama bertahun-tahun, pikir Hana,
merasa tersanjung dan gembira karena laki-
laki itu percaya padanya.
"Saat Takeo kembali dari Timur, Kaede
pasti akan tahu semua ini," ujar Hana.
"Masalah ini akan memisahkan mereka.
Kaede takkan memaafkannya. Aku
mengenalnya: Takeo akan melarikan diri dari
Kaede dan dari dunia ini, dia akan mencari
perlindungan di Terayama. Biara itu hampir
tidak dijaga. Takkan ada yang menduga kau
akan ke sana. Kau bisa mengejutkannya di
sana."
Mata Akio setengah terpejam. Lalu meng-
hembuskan napas panjang. "Itu satu-satunya
yang akan mengakhiri penderitaanku."
Hana tergoda oleh hasrat untuk memeluk
Akio, untuk meringankan sakit hati orang
itu: yakin bisa menghibur laki-laki itu atas
kematiania ragu untuk menyebutnya
sebagai pembunuhanistrinya. Namun
dengan hati-hati menyimpan kenikmatan ini
untuk masa yang akan datang. Ada hal lain
lagi yang ingin dibicarakannya dengan Akio.
"Hisao telah berhasil menempa senjata api
kecil yang bisa dibawa tersembunyi?" tanya
Hana. "Tak ada pun bisa mendekati Takeo
untuk bisa membunuhnya dengan pedang,
tapi senjata api bisa digunakan dari jauh,
kan?"
Akio mengangguk dan bicara dengan lebih
tenang, seolah lega topik pembicaraan sudah
berganti. "Dia sudah mengujinya di tepi
pantai. Jangkauannya lebih jauh dari panah,
dan peluru lebih cepat dibanding anak
panah." Sesaat Akio berhenti bicara. "Suami
Anda amat tertarik, senjata yang menyebab-
kan kematian ayahnya. Dia ingin Takeo mati
dengan cara yang sama memalukannya."
"Memang ada semacam keadilan di dalam-
nya," ujar Hana setuju. "Cukup menyenang-
kan. Tapi agar benar-benar berhasil, kau
pasti akan melatih Hisao secara khusus?
Sebaiknya dilakukan uji coba untuk
memastikan semua berjalan lancar, agar dia
tidak kehilangan nyali, agar bidikannya
benar-benar tepat."
"Apakah Lady Arai punya orang yang bisa
diusulkan?" Akio menatap langsung pada
Hana dan ketika tatapan mereka beradu, hati
Hana serasa melompat gembira.
"Sebenarnya aku memang punya," sahut-
nya pelan. "Mendekatlah dan aku akan
membisikkan namanya."
"Tidak perlu," sahutnya. "Aku bisa
menebaknya."
Tapi Akio akhirnya mendekat, begitu
dekat hingga Hana bisa mencium napasnya
serta mendengar detak jantungnya. Tak satu
pun dari keduanya bicara atau bergerak.
Angin menggetarkan layar kasa, dan dari arah
pelabuhan terdengar jerit burung camar.
Setelah beberapa saat, Hana mendengar
suara Zenko dari pelataran.
"Suamiku sudah kembali," katanya, sambil
berdiri, tak yakin apakah merasa lega atau
kecewa.
***
Lord dan Lady Arai sering bepergian antara
Kumamoto dan Hofu, maka kedatangan
mereka di kota itu tidak lama setelah
kembalinya orang-orang asing, tidaklah
mengherankan. Kapal yang ditumpangi para
orang asing segera berangkat lagi menuju
Akashi bersama Shigeko, Sugita Hiroshi dan
kirin. Penduduk Hagi melepas kepergian
kirin dengan rasa bangga dan sedih; mereka
telah merasa memiliki hewan itu sejak
kedatangannya yang mencengangkan di
pelabuhan mereka. Tak lama kemudian,
Terada Fumio bersiap berlayar untuk
bergabung dengan ayahnya, Fumifusa, di
teluk, bersama dengan armada Otori.
Orang-orang asing sudah sering ber-
kunjung ke tempat Lord Arai sehingga tidak
menarik perhatian. Perbincangan mengalir
lebih lancar karena si jurubahasa makin
berani dan percaya diri, dan Don Carlo pun
makin fasih.
"Anda pasti mengira kami bodoh,"
katanya, "karena tidak mengetahui ada
Kaisar. Kini kami sadar kalau kami harus
mendekati beliau karena kami adalah utusan
raja kami, dan monarki harus berhadapan
dengan monarki."
Hana tersenyum. "Lord Kono yang baru-
baru ini kembali ke ibukota, dan yang pernah
bertemu Anda berdua, adalah keluarga
kekaisaran. Dia meyakinkan kami bahwa
Lord Arai mendapat dukungan Kaisar.
Kepemimpinan Lord Otori di Tiga Negara
dianggap tidak sah, maka dia hendak meng-
ajukan pembelaan atas tuduhan itu."
Don Joao nampak tertarik saat kalimat ini
diterjemahkan. "Mungkinkah Lord Arai bisa
membantu kami mendekati Yang Mulia
Kaisar?"
"Akan kulakukan dengan senang hati,"
sahut Zenko, wajahnya bersemu merah
karena gembira dan juga karena minum sake.
Perempuan itu, si jurubahasa, mener-
jemahkan kalimat ini, lalu mengatakan
beberapa kalimat lagi. Don Carlo tersenyum
agak sedih, Hana pikir, lalu menganggukkan
kepala dua atau tiga kali.
"Apa yang kau katakan?" tanya Hana
langsung pada Madaren.
"Maaf, Lady Arai. Aku bicara soal masalah
keagamaan pada Don Carlo."
"Ceritakan lebih banyak lagi pada kami.
Kami tertarik pada ajaran para orang asing,
dan terbuka dengan kepercayaan mereka."
"Tidak seperti Lord Otori," kata Don
Carlo. "Tadinya aku mengira dia akan ber-
sikap simpatik, dan aku menaruh harapan
besar untuk penyelamatan jiwa dari dosa dan
kematian bagi istrinya yang cantik itu, tapi
dia melarang kami menyebarkan agama
secara terang-terangan atau membangun
gereja."
"Kami tertarik mendengarkan masalah
ini," ujar Hana sopan. "Dan sebagai
imbalannya kami ingin tahu berapa banyak
kapal yang dimiliki raja Anda di Kepulauan
Kecil Selatan, dan berapa lama waktu yang
dibutuhkan untuk berlayar dari sini ke sana."
"Kau punya rencana baru," kata Zenko
malam itu saat mereka hanya berdua saja.
"Aku tahu sedikit tentang kepercayaan
orang-orang asing itu. Alasan mengapa kaum
Hidden selalu dibenci adalah karena mereka
lebih mematuhi Tuhan Rahasia ketimbang
penguasa mana pun. Deus milik orang-orang
asing itu juga sama, menuntut kesetiaan yang
utuh."
"Aku telah bersumpah setia berulang kali
pada Takeo," ujar Zenko. "Aku tidak
menyukai gagasan dikenal sebagai pelanggar
sumpah, seperti Noguchi: kukatakan yang se-
sungguhnya padamu, hanya itu yang masih
menahanku."
"Takeo telah menolak Deussudah jelas
dari apa yang kita dengar tadi. Bagaimana
kalau Deus memilihmu untuk menghukum-
nya?"
Zenko tertawa. "Bila Deus membawa-
kanku kapal dan senjata, maka aku siap ber-
hadapan dengannya!"
"Bila Kaisar sekaligus Deus memerintah-
kan kita untuk menghancurkan Takeo,
bagaimana kita bisa membantah atau tidak
mematuhinya?" ujar Hana. "Kita memiliki
restu; juga peralatan." Tatapan mereka ber-
temu, lalu mereka berdua tertawa terbahak-
bahak.
***
"Aku ada satu rencana lagi," kata Hana
kemudian, ketika kota sudah sunyi, dan dia
berbaring di pelukan suaminya, setengah
tertidur dan merasa puas.
Zenko sudah hampir tertidur. "Kau
memang sarang berharga dari gagasan yang
baik," sahutnya, seraya membelai istrinya
dengan malas.
"Terima kasih, tuanku! Tapi apakah kau
tidak ingin mendengarnya?"
"Tidak bisakah menunggu sampai besok?"
"Ada beberapa hal yang lebih baik di-
bicarakan dalam kegelapan."
Zenko menguap dan berpaling ke arah
istrinya. "Bisikkan rencanamu itu dan aku
akan mempertimbangkannya dalam mimpi-
ku."
Setelah Hana memberi tahukan, Zenko
terbaring dalam waktu lama tanpa bicara
hingga seperti sudah tertidur, namun Hana
tahu kalau suaminya itu masih terjaga. Akhir-
nya Zenko berkata, "Aku akan berikan dia
satu kesempatan lagi. Bagaimana pun, dia
adikku."*
Meskipun Sada telah berusaha, ditambah
salep dari Ishida, luka di wajah Maya tetap
berbekas, garis kemerahan di tulang pipinya
bak bayangan daun perilla. Maya dihukum
dengan berbagai cara atas ketidakpatuhan-
nya. Meskipun dia dipaksa melakukan tugas
paling rendah di rumah, dilarang bicara,
dilarang tidur dan makan, dia tetap lakukan
semua ini tanpa dendam, sadar kalau ia
memang pantas dihukum karena menyerang
dan melukai ayahnya. Maya belum bertemu
Taku selama seminggu, dan walau Sada
merawat lukanya, tapi dia tidak bicara atau
pun memeluk serta membelainya seperti
yang diinginkan Maya. Sendirian sepanjang
waktu, dijauhi semua orang, Maya punya
banyak waktu untuk memikirkan apa yang
telah terjadi. Begitu teringat kalau ia telah
menyerang ayahnya, air mata berlinang.
Biasanya ia tidak pernah menangis: satu-
satunya yang diingatnya yaitu saat berada di
sumber air panas, bersama Takeo dan Miki,
ketika menceritakan pada ayahnya bagai-
mana cara membuat si kucing tertidur
dengan tatapan maut Kikuta.
Hanya ketika ada Ayah aku bisa menangis,
pikirnya.
Mungkin air mata adalah bagian dari
kemarahan. Ia ingat kemarahannya pada
ayahnya karena tidak mengatakan kalau
punya anak laki-laki, karena semua rahasia
yang mungkin disembunyikan ayah dari diri-
nya, karena semua muslihat yang terjadi
antara orangtua dan anaknya.
Namun Maya juga ingat kalau tatapannya
menguasai tatapan ayahnya, kalau ia bisa
mendengar langkah ringan dan merasakan
kehadiran ayahnya saat tidak kelihatan. Maya
melihat betapa kekuatan si kucing telah ber-
tambah dan memperkuat kekuataan dirinya.
Kekuatan itu masih saja menakutkan bagi-
nya, tapi setiap hari, di saat kurang tidur,
makan dan bicara, daya tarik kekuatan itu
semakin bertambah, dan mulai bisa melihat
bagaimana ia bisa mengendalikannya.
Di akhir minggu, Taku memanggilnya
dan mengatakan kalau mereka akan pergi ke
Hofu keesokan harinya.
"Kakakmu, Lady Shigeko, membawa
kuda-kuda," katanya. "Dia ingin mengucap-
kan selamat tinggal padamu."
Saat Maya hanya membungkuk hormat
tanpa menjawab, Taku berkata, "Kau boleh
bicara sekarang: hukumannya sudah selesai."
"Terima kasih, Guru," sahutnya dengan
patuh, kemudian berkata, "Aku benar-benar
menyesal."
"Kita semua pernah melakukan kesalahan
yang berbahaya. Aku yakin kalau aku pernah
menceritakan saat ayahmu menangkapku di
Shuho."
Maya tersenyum. Kedua saudara perem-
puannya senang sekali mendengarkan cerita
itu saat mereka masih kecil. "Shizuka sering
menceritakannya pada kami, untuk memper-
ingatkan agar kami patuh!"
"Kami berdua beruntung karena ayahmu
yang kami hadapi. Jangan lupa, kebanyakan
orang Tribe dewasa akan membunuh tanpa
pikir panjang, anak-anak atau bukan."
***
Shigeko membawa dua kuda betina tua
Maruyama, untuk Maya dan Sada, satu
berwarna coklat kemerahan, dan satunya lagi,
yang membuat Maya kegirangan, berwarna
abu-abu pucat dengan surai dan ekor hitam,
sangat mirip kuda tua milik Taku, Ryume,
anak Raku.
"Ya, yang abu-abu ini bisa menjadi milik-
mu," sahut Shigeko, memerhatikan mata
Maya yang berbinar. "Tapi, kau harus
merawatnya baik-baik selama musim
dingin." Shigeko melihat wajah Maya:
"Sekarang aku bisa bedakan antara kau dan
Miki." Sambil menarik Maya ke samping,
Shigeko berkata pelan, "Ayah menceritakan
apa yang terjadi. Aku tahu ini sulit bagimu,
melakukan semua yang diminta Taku dan
Sada. Buka mata dan telingamu lebar-lebar
saat tiba di Hofu. Aku yakin kau bisa
berguna di sana." Kedua kakak beradik itu
berpelukan; setelah mereka berpisah, Maya
merasa diperkuat oleh kepercayaan Shigeko
kepadanya. Itulah yang membuatnya mampu
bertahan selama musim dingin yang panjang
di Hofu, saat angin dingin terus berhembus
dari laut, bukannya membawa salju sebagai-
mana mestinya tapi malah membawa hujan
es dan hujan sedingin es. Bulu kucing itu
terasa hangat, dan Maya kerap tergoda untuk
memanfaatkannya. Awalnya masih terasa
janggal, lalu dengan rasa percaya diri yang
makin besar, Maya belajar memaksa roh
kucing itu tunduk pada kehendaknya. Masih
ada banyak unsur ruang antara dua dunia
yang menakutkan baginya: hantu yang
kelaparan dengan keinginan yang belum
terpuaskan, serta kesadarannya tentang
semacam kepandaian yang mencari dirinya.
Rasanya seperti kilatan halilintar di kege-
lapan. Kadang ia menatap dunia itu dan
merasakan daya tariknya, tapi seringkali ia
menjauhi kilauannya, tetap berada di balik
bayang-bayang. Sesekali ia bisa menangkap
penggalan kata, bisikan yang tak kunjung ia
pahami.
Satu hal yang menyita pikirannya se-
panjang musim dingin adalah masalah yang
membuat ia sangat marah pada ayahnya:
bocah misterius yang merupakan kakak
tirinya, yang tidak pernah dibicarakan siapa
pun, yang kata Taku akan membunuh
ayahnyaayahnya! Saat ia memikirkan
tentang bocah itu, ia menjadi bingung dan
roh si kucing berusaha menguasai dirinya
dan melakukan apa yang diinginkannya.
Ia sering terbangun berteriak karena
mimpi buruk, sendirian di kamar karena kini
setiap malam Sada bersama Taku. Maya
berbaring terjaga sampai pagi, takut meme-
jamkan mata. Sada mengatur agar mereka
tinggal di rumah keluarga Muto antara
sungai dan kediaman Zenko. Rumah itu
dulunya adalah tempat penyulingan sake,
tapi dengan makin bertambahnya pelanggan
karena Hofu kian makmur, keluarga itu
pindah ke bangunan yang lebih besar, dan
bangunan ini kini hanya dijadikan gudang.
Seperti di Maruyama, keluarga Muto
menyediakan penjaga dan pelayan, dan Maya
masih berpakaian anak laki-laki di luar
rumah, tapi diperlakukan sebagai anak
perempuan ketika di dalam rumah. Teringat
pesan Shigeko, dan ia membuka telinga
lebar-lebar, mendengarkan bisik-bisik per-
cakapan di sekelilingnya, berjalan-jaian me-
lewati pelabuhan saat cuaca cukup cerah, dan
memberitahu Taku dan Sada apa yang
didengarnya. Tapi ia tidak menceritakan
semuanya: sebagian dari desas-desus yang
mengejutkan dan membuatnya marah
sehingga ia tidak ingin mengulang kata-kata
itu. Ataupun berani bertanya pada Taku
tentang pemuda yang merupakan kakaknya
itu.
Maya bertemu Shigeko lagi sebentar ketika
musim semi, ketika kakaknya berlayar
bersama kirin dan Hiroshi dalam perjalanan
ke Miyako. Ia sudah sangat terbiasa dengan
segala hasrat Taku terhadap Sada, lalu
mengamati kakaknya dan Hiroshi untuk
melihat apakah mereka menunjukkan gejala
yang sama. Terasa sudah begitu lama ketika
ia dan Miki menggoda Shigeko tentang
Hiroshi: apakah hanya sekadar rasa tertarik
seorang gadis belia, ataukah kakaknya masih
tetap mencintai pemuda yang kini menjadi
pengawal seniornya? Dan apakah Hiroshi
mencintai kakaknya? Seperti halnya Takeo,
Maya juga memerhatikan reaksi cepat
Hiroshi sewaktu Tenba melompat dan
mundur tiba-tiba karena takut selama
upacara di Maruyama, dan menarik
kesimpulan yang sama. Kini ia kurang yakin:
di satu sisi, Shigeko dan Hiroshi tampak
saling menjauh sekaligus bersikap resmi; di
sisi lain mereka seperti saling memahami
pikiran masing-masing, dan ada semacam
keselarasan yang terjalin di antara mereka.
Shigeko telah mengemban wewenang baru,
dan Maya tak berani lagi menggoda maupun
bertanya padanya.
Di bulan keempat, setelah Shigeko dan
Hiroshi pergi bersama kirin menuju Akashi,
Taku disibukkan dengan permintaan dari
orang-orang asing yang telah kembali dari
Hagi dan bersemangat untuk membangun
pos perdagangan secepatnya. Kira-kira di saat
inilah Maya sadar atas perubahan yang
terjadi dengan perlahan sejak hari pertama
musim semi. Semua perubahan itu seperti
memastikan desas-desus yang mulai di-
dengarnya saat musim dingin.
Sejak kecil ia sudah hidup dengan
kepercayan bahwa kesetiaan keluarga Muto
teguh kukuh terhadap Klan Otori, dan
bahwa Muto mengendalikan kesetiaan
Tribeterlepas dari Kikuta yang membenci
dan berusaha membunuh ayahnya. Shizuka,
Kenji, dan Taku adalah keluarga Muto dan
telah menjadi penasihat terdekat keluarga
Otori dan telah menjadi gurunya. Maka
butuh waktu lama baginya untuk dapat
memahami dan menerima gejala-gejala yang
tampak di depan matanya.
Kurir pembawa pesan yang datang ke
rumah jumlahnya makin sedikit; informasi
yang diantar amat terlambat hingga akhimya
tidak berguna. Para penjaga tertawa sinis di
belakang Taku tentang obsesinya terhadap
Sada: laki-laki-perempuan yang lemah dan
gila. Maya menemukan dirinya terbebani
dengan lebih banyak pekerjaan karena para
pelayan makin malas, bahkan kurang ajar.
Seiring makin besar kecurigaannya, diikuti-
nya para pelayan ke penginapan dan men-
dengar cerita-cerita mereka: kalau Taku dan
Sada adalah penyihir, dan kedua orang itu
memanfaatkan arwah kucing dalam mantra-
mantra mereka.
Sewaktu di penginapan itulah Maya men-
dengar percakapan lain di kalangan keluarga
Muto, Kuroda dan Imai: setelah lima belas
tahun dalam damai, ketika pedagang dan
petani biasa menikmati kesejahteraan, Tribe
mulai menyesal karena sebelumnya mereka
yang menguasai perdagangan, dan ketika
bangsawan memanfaatkan ketrampilan
mereka.
Sumpah setia tidak pasti yang digabung
Kenji dengan kekerasan karakternya,
pengalaman dan akal bulusnya mulai hancur,
dan untuk memperbaikinya saat ini, maka
Kikuta Akio muncul dari pengasingan.
Maya mendengar nama laki-laki itu
beberapa kali di awal-awal bulan keempat,
dan setiap kali didengarnya, ketertarikan dan
keingintahuannya semakin bertambah. Satu
malam, sesaat sebelum bulan purnama, ia
pergi diam-diam ke penginapan di tepi
sungai, saat itu kota terasa lebih hidup dari
biasanya karena Zenko dan Hana sudah
kembali bersama rombongan, dan
penginapan penuh sesak dengan orang.
Maya menyembunyikan diri di bawah
beranda, menggunakan kemampuan meng-
hilang untuk menyelinap di bawahnya;
malam ini terlalu bising untuk bisa
mendengar banyak bahkan dengan telinga-
nya yang tajam, tapi ia menangkap kata
ketua Kikuta, dan sadar kalau Akio ada di
penginapan itu.
Ia terkejut temyata laki-laki itu berani
muncul secara terang-terangan di Hofu, dan
bahkan lebih kagum lagi ternyata begitu
banyak orang yang ia kenal dari kalangan
Tribe bukan hanya mentolerir kehadirannya,
tapi justru mencarinya, memperkenalkan diri
pada Akio. Maya menyadari kalau orang itu
berada dalam perlindungan Zenko, dan ia
bahkan mendengar Zenko disebut sebagai
ketua Muto. Ia tahu kalau itu pengkhianatan,
meski ia tak tahu sampai sejauh mana
kebenarannya. Selama ini ia dapat meng-
hilang diri tanpa diketahui, dan menjadi
sombong karenanya. Ia meraba pisau di baju
luamya lalu menggunakan kemampuan
menghilang kemudian berjalan ke pintu
penginapan.
Semua pintu terbuka lebar, membiarkan
angin sepoi-sepoi dari arah barat daya masuk.
Lentera menyala berasap, dan udara terasa
pekat dengan berbagai aroma, ikan panggang
dan sake, minyak wijen serta jahe.
Maya memindai berbagai kelompok;
langsung tahu mana yang bernama Akio
karena laki-laki itu melihat dirinya, langsung
menembus kemampuan menghilangnya. Saat
itu ia menyadari betapa berbahayanya laki-
laki itu, betapa lemah dirinya bila dibanding-
kan dengan Akio, betapa laki-laki itu bisa
membunuhnya tanpa ragu. Akio melompat
dari lantai dan seperti terbang ke arahnya,
melemparkan senjata selagi bergerak. Maya
melihat kilau pisau, mendengar desingnya di
udara, dan tanpa pikir panjang ia men-
jatuhkan diri ke lantai. Semua yang ada di
sekelilingnya berubah: ia melihat dengan
mata si kucing; dirasakannya tekstur lantai di
bawah kakinya; cakarnya di lantai papan
beranda sewaktu ia melompat melarikan diri
ke dalam gelapnya malam.
Di belakangnya, Maya menyadari ke-
hadiran pemuda itu, Hisao. Dirasakannya
tatapan pemuda itu mencarinya, dan men-
dengar penggalan suara yang membentuk
kata-kata. Saat memahami kata-kata itu, ia
ketakutan setengah mati. Datanglah padaku.
Sudah lama aku menunggumu.
Dan si kucing hanya ingin kembali pada
pemuda itu.
Maya melarikan diri pada satu-satunya
perlindungan yang dikenalnya, pada Sada
dan Taku, membangunkan keduanya dari
tidur nyenyak. Mereka berusaha menenang-
kan saat dia berjuang sekuat tenaga men-
dapatkan kembali wujud manusianya, Sada
memanggil-manggil namanya sementara
Taku menatap matanya, melawan tatapan
Maya yang amat kuat. Akhirnya tubuh Maya
lemas; sepertinya tertidur selama beberapa
saat. Ketika membuka mata, dia bisa berpikir
jelas lagi, dan ingin menceritakan segalanya
pada mereka.
Taku mendengarkan tanpa bicara selagi
Maya menceritakan apa yang didengarnya.
Taku mengagumi pengendalian diri gadis itu
yang dapat menceritakan tanpa meneteskan
air mata.
"Jadi sesuatu menghubungkan Hisao dan
kucing itu?" akhimya ia bertanya.
"Dialah yang memanggil kucing itu," ujar
Maya pelan. "Dialah penguasa si kucing."
"Penguasa si kucing? Darimana kau dapat
kata itu?"
"Itulah yang dikatakan para hantu, jika
kubiarkan mereka bicara."
Taku menggelengkan kepala dengan
tatapan bertanya-tanya. "Kau tahu siapa
Hisao itu?"
"Dia cucu Muto Kenji." Ia berhenti
sejenak lalu bicara tanpa perasaan, "Putra
ayahku."
"Sudah berapa lama kau tahu?"
"Aku pernah mendengar kau mengatakan
pada Sada, di Maruyama pada musim gugur
yang lalu," jawab Maya.
"Pertama kali kita melihat kucing itu,"
bisik Sada.
"Hisao pasti seorang penguasa alam baka,"
ujar Taku, mendengar Sada menghela napas,
hembusan napasnya terasa di bulu kuduknya.
"Kukira hal itu hanya legenda."
"Apa artinya itu?" tanya Maya.
"Artinya dia mampu untuk berjalan di
antara dua dunia, mendengar suara orang
yang sudah mati. Para arwah akan patuh
padanya. Dia memiliki kekuatan untuk me-
nenangkan atau menghasut mereka. Ini jauh
lebih buruk dari yang kita bayangkan."
Inilah pertama kalinya Taku merasakan
ketakutan yang sesungguhnya. Takut pada
kekuatan supranatural, gelisah atas peng-
khianatan yang telah diungkap Maya, dan
kemarahan pada rasa puas dalam dirinya serta
kurang waspada.
"Apa yang harus kita lakukan?" tanya Sada
pelan. Sada merengkuh dan memeluk Maya
erat-erat. Tatapan Maya yang berkilat ter-
paku pada wajah Taku.
"Kita harus membawa Maya pergi,"
sahutnya. "Tapi aku harus menemui kakakku
lebih dulu, membuat satu tuntutan terakhir
padanya, dan mencari tahu seberapa dalam
keterlibatannya dengan Akio, dan berapa
banyak yang mereka tahu tentang Hisao.
Dugaanku adalah mereka belum mengetahui
bakatnya. Tidak ada lagi orang yang tahu
tentang hal semacam ini di kalangan Tribe:
semua laporan kita menunjukkan kalau
Hisao tidak memiliki kemampuan Tribe."
Apakah Kenji tahu? Taku memikirkan hal
itu, dan menyadari sekali lagi betapa ia sangat
merindukan Gurunya itu, dan betapa besar
kegagalannya untuk bisa menggantikan
kedudukan gurunya itu.
"Kita akan pergi ke Inuyama," katanya.
"Aku akan menemui Zenko besok, tapi kita
harus tetap pergi. Kita harus bawa Maya
pergi."
"Kita belum mendapat kabar dari Lord
Takeo sejak Terada datang dari Hagi," kata
Sada gelisah.
"Sebelumnya aku tidak cemas," sahut
Taku, dicekam perasaan kalau segala
sesuatunya akan terurai satu demi satu.
***
Saat malam lebih larut, meski sulit untuk
mengakui pada dirinya sendiri, terlebih lagi
mengaiakannya pada Sada atau orang lain,
keyakinannya makin besar kalau Takeo akan
hancur, kalau jaring mulai makin kencang di
sekelilingnya dan tak ada jalan untuk lolos.
Saat terjaga, sadar akan tubuh tinggi Sada di
sisinya, mengamati malam yang pucat, Taku
berpikir keras apa yang harus dilakukan.
Rasanya masuk akal mematuhi kakaknya
yang akan mengambil alih kepemimpinan
Tribeatau bahkan menyerahkan jabatan
itu pada Taku sendiri: keluarga Muto dan
Kikuta bisa berdamai; maka ia tak harus
menyerahkan nyawa Sada atau nyawanya
sendiri; naluri pragmatis Muto mendesaknya
untuk mengikuti jalan ini. Ia berusaha
menimbang apa saja yang dipertaruhkan.
Nyawa Takeo, pastinya. Juga nyawa Kaede,
kemungkinan anak-anak jugamungkin
Shigeko tidak, kecuali bila dia melawan, tapi
Zenko pasti menganggap si kembar terlalu
berbahaya. Jika Takeo melawan balik, berarti
kematian beberapa ribu prajurit Otori yang
tak ada hubungan dengan dirinya. Hiroshi...
Memikirkan Hiroshi telah membuatnya
berhenti secara tiba-tiba. Sebagai anak laki-
laki, Taku punya rasa iri yang terpendam
pada Hiroshi, terhadap sifat ksatria yang
jujur, keberanian fisiknya, kesadaran ter-
goyahkan pada kehormatan dan kesetiaan. Ia
selalu berusaha membuat Hiroshi terkesan;
menyayangi sahabatnya itu lebih dari apa
pun, sebelum ia bertemu Sada. Ia tahu kalau
Hiroshi lebih memilih mencabut nyawanya
ketimbang meninggalkan Takeo, dan ia tak
tahan membayangkan wajah Hiroshi saat
sadar kalau ia berpihak pada Zenko.
Alangkah bodohnya kakakku, pikirnya,
bukan untuk yang pertama kalinya. Ia
menyesalkan tindakan kakaknya yang
menempatkan ia dalam posisi serba salah.
Direngkuhnya Sada erat. Tak pernah ku-
bayangkan kalau aku akan jatuh cinta,
pikirnya saat membangunkan Sada dengan
lembut, dan meskipun tidak tahu kalau
itulah terakhir kalinya dia membangunkan
Sada. Tak pernah kubayangkan kalau aku
akan menjadi ksatria yang mulia.
***
Taku mengirim pesan keesokan harinya, dan
menerima jawabannya sebelum tengah hari.
Ia diperlakukan dengan santun seperti biasa,
dan diundang ke kediaman di Hofu untuk
makan malam bersama Zenko dan Hana.
Dia menghabiskan waktu dengan mem-
persiapkan diri untuk bepergian, tidak secara
terang-terangan, karena tak ingin menarik
perhatian. Taku berkuda pergi bersama
empat orang yang telah menemaninya sejak
dari Inuyama, lebih memercayai mereka
ketimbang orang yang disediakan keluarga
Muto di Hofu.
Begitu bertemu, Taku melihat ada
perubahan dalam diri kakaknya. Kumis dan
janggut Zenko tampak lebih lebat, tapi lebih
dari itu, sang kakak menunjukkan kepercaya-
an diri yang baru, dengan langkah yang lebih
angkuh. Taku juga memerhatikan, walau tak
langsung mengomentari, kalau Zenko
mengenakan kalung dari untaian rosario
indah yang terbuat dari ukiran gading, mirip
yang dipakai Don Joao dan Don Carlo yang
juga hadir saat makan malam. Sebelum mulai
makan, Don Carlo diminta untuk meng-
ucapkan doa. Zenko dan Hana duduk
dengan tangan terkatup, kepala tertunduk,
serta tampak hikmad.
Taku memerhatikan kehangatan baru
antara kedua orang asing itu dengan Zenko.
Mendengar betapa sering Deus diucapkan,
dan menyadari dengan campuran antara rasa
tercengang dan jijik kalau kakaknya telah
mengikuti kepercayaan orang asing.
Berpindah agama atau hanya berpura-pura?
Taku tidak percaya kalau tindakan Zenko
tulus adanya. Ia mengenal kakaknya sebagai
laki-laki tanpa agama dan tidak berminat
pada sesuatu yang berbau spiritualsama
seperti dirinya. Rupanya Zenko melihat ada
keuntungan: pasti berhubungan dengan
militer, pikirnya, dan kemarahannya muncul
selagi memikirkan kalau yang bisa diberikan
orang asing itu adalah senjata api dan kapal.
Zenko menyadari kegelisahan Taku yang
makin bertambah, dan ketika makan malam
selesai dia berkata, "Ada yang harus kubicara-
kan dengan adikku. Kami permisi sebentar.
Taku, ikutlah ke taman. Malam ini indah:
sudah hampir purnama."
Taku mengikuti, membuka semua indera-
nya, memasang pendengarannya untuk
langkah kaki yang tak dikenal, hembusan
napas yang tak terduga. Apakah sudah ada
pembunuh yang bersembunyi di taman, dan
kakaknya membimbing ia ke dalam
jangkauan pisau lempar mereka? Atau senjata
mereka? Dan bulu kuduknya merinding
memikirkan senjata yang bisa membawa
kematian dari jarak jauh, yang bahkan tidak
terdeteksi oleh semua kemampuan Tribe.
Zenko berkata, seolah bisa membaca
pikirannya, "Tak ada alasan bagi kita untuk
bermusuhan. Janganlah kita saling mem-
bunuh."
"Kurasa kau tengah merencanakan per-
sekongkolan menentang Lord Otori," sahut
Taku, seraya menyembunyikan marahnya.
"Tak bisa kubayangkan apa alasannya, karena
kau telah bersumpah setia dan berutang
nyawa padanya, juga karena tindakan ini
akan membahayakan keluargamuibu kita,
akubahkan kedua putramu. Mengapa
Kikuta Akio berada di Hofu dan dalam
perlindunganmu? Perjanjian keji apa yang
kau buat dengan orang-orang ini?" Taku
memberi isyarat ke arah tempat percakapan
orang asing itu terdengarseperti pekikan
burung, pikirnya kecut.
"Tidak ada kejahatan di dalamnya," sahut
Zenko, mengacuhkan pertanyaan tentang
Akio. "Aku melihat kebenaran dalam
kepercayaan mereka dan aku memilih untuk
mengikuti jalan mereka. Kebebasan itu
diperbolehkan di seluruh Tiga Negara,
kurasa."
Taku melihat deretan gigi putih di atas
janggut Zenko saat tersenyum. Ia ingin
langsung menyerang, namun menahan diri.
"Dan sebagai imbalannya?"
"Aku terkejut kau belum tahu, tapi aku
yakin kau bisa menebaknya." Zenko
menatapnya, lalu mendekat dan memegang
tangannya. "Taku, kita bersaudara, dan aku
sayang padamu, terlepas dari perbedaan
pendapat kita. Mari kita bicara terns terang.
Takeo tidak punya masa depan: mengapa
ikut jatuh bersamanya? Bergabunglah
denganku: Tribe akan bersatu kembali: aku
pernah bilang kalau aku punya orang dalam
di kalangan Kikuta. Bukan rahasia lagi kalau
menurutku alasan Akio sangat masuk akal.
Dia akan mengabaikan peranmu dalam
kematian Kotaro: semua orang tahu saat itu
kau masih kecil. Akan kupenuhi semua
keinginanmu. Takeo yang menyebabkan
kematian ayah kita. Tugas pertama kita
adalah balas dendam atas kematian itu."
"Ayah kita memang pantas mati," sahut
Taku, seraya menahan kata-katanya. Dan kau
juga pantas mati.
"Tidak, Takeo itu penipu, perebut
kekuasaan, juga pembunuh. Ayah kita
seorang ksatria sejati."
"Kau memandang Takeo seolah kau ber-
kaca," sahut Taku. "Kau melihat bayangan
dirimu sendiri. Kaulah si perebut kekuasa-
an."
Taku merasa jarinya gatal ingin meraih
pedang, dan tubuhnya terasa perih seakan
siap menghilang. Yakin kalau Zenko pasti
hendak membunuhnya saat ini. Taku
tergoda untuk menyerang, begitu kuatnya
godaan itu hingga ia hampir tak sanggup
menahannya, namun ada sesuatu yang
mencegahnya: rasa enggan untuk mencabut
nyawa kakaknya, dan teringat kata-kata
Takeo: Saudara saling membunuh, sungguh
tak terbayangkan, Kakakmu, seperti layaknya
orang lain, termasuk dirimu sendiri, Taku
sayang, harus taat pada hukum.
Taku menghirup napas dalam-dalam.
"Katakan apa yang kau inginkan dari Lord
Otori. Mari kita rundingkan."
"Tak ada yang bisa dirundingkan kecuali
dengan kehancuran dan kematiannya," sahut
Zenko marah. "Dalam hal ini, terserah
apakah kau memihak atau menentangku."
Taku mundur dengan sikap hati-hati.
"Biar kupertimbangkan dulu. Aku akan
bicara lagi denganmu besok. Dan kau juga,
pikirkan semua tindakanmu. Apakah
keinginan balas dendammu bisa menjamin
tidak akan menyebabkan perang saudara?"
"Baiklah," ujar Zenko. "Oh ya, sebelum
kau pergi: aku lupa berikan ini padamu."
Dikeluarkannya wadah bambu dari balik
jubah dan menyerahkannya. Taku meng-
ambilnya dengan firasat: dikenalinya benda
itu sebagai tempat surat, yang digunakan di
Tiga Negara. Bagian bawahnya direkatkan
dengan lilin dan dicap dengan lencana Otori,
tapi yang satu ini sudah terbuka.
"Kurasa ini dari Lord Otori," ujar Zenko,
lalu tertawa. "Kuharap ini bisa memengaruhi
keputusanmu."
Taku berjalan dengan cepat dari taman,
berharap setiap waktu mendengar anak
panah atau pisau melesat di udara; ia
meninggalkan kediaman tanpa pamitan. Para
penjaga menunggu di gerbang dengan kuda-
kuda. Diraihnya tali kekang Ryume lalu
bergegas naik.
"Lord Muto," laki-laki di sebelahnya
berkata pelan.
"Ada apa?"
"Kuda Anda tadi batuk-batuk, seakan sulit
bernapas."
"Mungkin karena udara musim semi.
Udara terasa sulit dihirup dengan pekatnya
serbuk sari." Disingkirkannya kecemasan
laki-laki itu, dikalahkan dengan kecemasan
yang lebih besar dalam dirinya.
Di tempat penginapannya, dia meminta
agar pelana kuda jangan dibuka, dan
menyiapkan dua kuda betina. Kemudian
Taku masuk ke tempat Sada tengah
menunggu. Sada masih berpakaian lengkap.
"Kita pergi sekarang," kata Taku padanya.
"Apa yang kau temukan?"
"Zenko bukan hanya membuat
kesepakatan dengan Akio, tapi juga telah
bersekutu dengan orang asing. Dia mengaku
telah menerima agama mereka, dan sebagai
imbalannya mereka mempersenjatainya."
Diserahkannya wadah surat pada Sada. "Dia
mengacaukan surat-surat yang Takeo kirim.
Itu sebabnya tidak ada kabar darinya."
Sada mengambil tabung itu lalu
mengeluarkan suratnya. Dia membaca
dengan cepat tulisan dalam surat itu. "Takeo
memintamu agar segera menemuinya di
Inuyamatapi ini sudah terlambat selama
berminggu-minggu. Tentunya dia sudah
berangkat saat ini?"
"Kita harus ke sana malam ini. Bulan
purnama cukup terang untuk berkuda. Bila
Takeo telah meninggalkan Inuyama, maka
aku harus mengejarnya sampai di perbatasan.
Dia harus kembali dan membawa pasukan
kembali dari wilayah Timur. Bangunkan
Maya; dia harus ikut. Aku tak ingin dia
ditemukan Akio. Di Inuyama kalian lebih
aman."
***
Maya tengah mimpi aneh serba merah di
mana kakak laki-lakinya, yang wajahnya kini
bisa dilihat sekilas, muncul dalam berbagai
samaran, terkadang ditemani para arwah.
Kakaknya itu tampak kejam, membawa
senjata yang menakutkan. Tatapannya mem-
buat Maya merasakan ketakutan yang tak
bisa dijelaskan, seolah Hisao tahu semua
rahasia dalam dirinya. Kakaknya itu memiliki
semacam jiwa kucing seperti dirinya. Malam
ini Hisao membisikkan nama Maya, yang
membuatnya ketakutan; karena tak tahu
kalau Hisao mengenalnya; Maya terbangun
dan sadar kalau Sada yang bicara pelan di
telinganya.
"Bangunlah, lekas berpakaian. Kita pergi
sekarang."
Tanpa bertanya, Maya melakukan seperti
yang diminta karena bulan-bulan musim
dingin telah mengajarkannya untuk patuh.
"Kita akan ke Inuyama untuk menemui
ayahmu," kata Taku selagi mengayunkan
tubuh Maya ke punggung kuda.
"Mengapa kita pergi di malam seperti ini?"
"Aku tidak ingin menunggu sampai pagi."
Selagi kuda-kuda berderap menyusuri
jalan menuju jalan besar, Sada bertanya pada
Taku, "Apakah kakakmu membiarkan kau
pergi?"
"Itu sebabnya kita pergi sekarang. Dia bisa
saja menyerang atau membuntuti. Ber-
siagalah dengan senjata, dan bersiap untuk
bertarung. Aku curiga ada jebakan."
Hofu bukanlah kota yang dikelilingi
dinding, dan kegiatan perdagangan dan
pelabuhan berarti orang datang dan pergi
pada jam berapa saja, mengikuti bulan dan
gelombang; di malam seperti ini, di awal
musim semi dengan bulan yang hampir
penuh, ada pelancong lain di jalan, dan
sekelompok kecil orangTaku, Sada, Maya
serta empat pengawaltidak diberhentikan
atau ditanyai. Tak lama setelah matahari
terbit, mereka berhenti di sebuah penginapan
untuk sarapan dan minum teh.
Segera setelah mereka hanya bertiga di
ruang makan kecil, Maya berkata pada Taku,
"Apa yang terjadi?"
"Akan kuceritakan sedikit saja demi
keselamatanmu. Pamanmu Arai dan istrinya
berkomplot menentang ayahmu. Kami
mengira bisa membendungnya, tapi men-
dadak situasinya makin mengancam.
Ayahmu harus segera kembali."
Kelelahan tergambar di wajah Taku, dan
suaranya terdengar sangat serius.
"Bagaimana bisa paman dan bibi ber-
tindak begitu, saat putra mereka tinggal di
rumah kami?" tanya Maya gusar. "Ibu harus
diberitahu. Kedua bocah itu harus mati!"
"Kau kedengaran sangat berbeda dengan
ayahmu," kata Sada. "Darimana datangnya
kekejaman itu?" Tapi suaranya terdengar
penuh kasih sayang dan kekaguman.
"Ayahmu berharap tak seorang pun harus
mati," tutur Taku. "Itu sebabnya kita harus
menyuruhnya kembali. Hanya ayahmu yang
memiliki reputasi dan kekuatan untuk
mencegah pecahnya perang."
"Lagipula, Hana memang akan ke Hagi
hari ini." Sada menarik Maya dan duduk
dengan merangkulnya. "Selama musim panas
ini Hana akan bersama ibumu dan adikmu."
"Itu lebih buruk lagi! Ibu harus di-
peringatkan. Aku akan ke Hagi dan men-
ceritakan pada Ibu tentang niat Hana yang
sebenarnya!"
"Tidak, kau harus tetap bersama kami,"
sahut Taku, merangkul bahu Sada. Mereka
duduk diam selama beberapa saat. Seperti
keluarga, pikir Maya. Aku tidak akan
melupakan ini: makanan yang terasa begitu
lezat saat aku begitu lapar, harumnya aroma
ten, merasakan angin musim semi, cahaya
matahari yang berubah selagi gumpalan besar
awan putih berarak. Sada dan Taku
bersamaku, begitu bersemangat, begitu
pemberani, merasakan hari-hari yang kami
lalui dalam perjalanan, terus maju. Bahaya...
Cuaca hari itu tetap cerah dan segar. Kira-
kira tengah hari, angin sepoi-sepoi berhenti
berhembus, awan menghilang ke arah timur
laut, langit cerah, biru terang. Peluh
membuat kulit kuda menjadi lebih gelap di
bagian leher tubuh mereka selagi meninggal-
kan dataran pesisir dan mulai menanjak ke
perbatasan pertama. Hutan kian lebat di
sekeliling mereka; sesekali terdengar suara
jangkrik bak petikan alat musik. Maya mulai
merasa lelah. Irama berjalan kuda, hangatnya
senja membuatnya mengantuk. Ia mengira
tengah bermimpi, dan sekonyong-konyong
dilihatnya Hisao; lalu tersadar kaget.
"Ada yang mengikuti kita!"
Taku mengacungkan tangan, dan mereka
berhenti. Mereka mendengarnya: derap kaki
hewan dari lereng.
"Teruskan perjalanan dengan Maya," ujar
Taku pada Sada. "Kami akan menahan
mereka. Jumlah mereka paling banyak dua
belas orang. Kami akan segera menyusul."
Taku memberi perintah dengan cepat pada
pengawalnya; mereka mengambil busur dari
punggung, membelokkan kuda keluar dari
jalan dan menghilang di balik batang-batang
pohon bambu.
"Pergilah," perintah Taku pada Sada;
dengan enggan melajukan kuda dan Maya
mengikuti. Mereka berkuda dengan cepat
selama beberapa saat, tapi seiring dengan
kuda-kuda yang mulai lelah, Sada berhenti
lalu menengok ke belakang.
"Maya, apa yang kau dengar?"
Ia seperti mendergar dentingan baja,
ringkikan kuda, teriakan dan pekikan
pertarungan, dan satu suara lagi, dingin dan
brutal, yang bergenia sampai ke perbatasan,
membuat burung-buning memekik ke-
takutan lalu terbang. Sada juga men-
dengarnya.
"Mereka punya senjata api," serunya.
"Tetap di sinijangan, jalan terus, lalu
sembunyi. Aku harus kembali. Aku tak bisa
meninggalkan Taku."
"Aku juga," gumam Maya, membalikkan
kuda betina yang ketakutan ke arah mereka
datang, tapi di kejauhan mereka melihat
kepulan debu dan mendengar derap kuda,
melihat kuda berkulit abu-abu dan bersurai
hitam.
"Itu dia datang," teriak Sada lega.
Taku masih memegang pedang, lengannya
berlumuran darahdarahnya atau darah
orang lain, mustahil diketahui. Taku
meneriakkan sesuatu ketika melihat mereka,
tapi Maya tak memahaminya karena saat
mengucapkan kata-kata itu Ryume, kudanya,
jatuh; tertahan dengan lututnya, kemudian
terguling. Kejadiannya begitu cepat: Ryume
jatuh lalu mati, menghempaskan tubuh Taku
ke jalanan.
Secepatnya Sada menderapkan kuda
menghampiri. Kuda betina tunggangan Sada
mendengus dan menjadi liar saat melihat
kematian Ryume. Taku berusaha bangkit.
Sada menarik tali keitang kudanya agar
berhenti di samping Taku. Kemudian dia
meraih tangan Taku yang menggapai lalu
mengayunon tubuh Taku di belakangnya.
Dia baik-baik saja, pikir Maya lega. Dia
tak bisa melakukan itu bila dia terluka.
Taku tidak terlula parah, meski banyak
orang yang mati di jalanan di belakangnya,
pengawalnya dan sebagian besar penyerang-
nya. Dia merasakan sayatan yang sangat
menyakitkan di wajahnya, satu sayatan lagi di
tangannya yang memegang pedang. Dia
menyadari kuatnya punggung Sada saat
memeluknya, kemudian tembakan itu
meraung lagi. Dia merasakan tembakan itu
mengena lehernya dan menembusnya;
kemudian dia jatuh dan Sada jatuh
bersamanya, dan kuda menimpa tubuh
mereka. Dari kejauhan didengarnya Maya
berteriak. Pergilah, nak, pergi, Taku ingin
mengucapkannya, tapi tak sempat lagi.
Matanya dipenuhi cahaya langit biru yang
menyilaukan: cahaya matahari berputar-putar
dan kian redup. Waktunya telah tiba. Dia
nyaris tak sempat berpikir, aku sekarat, aku
harus berkonsentrasi pada kematian, sebelum
kegelapan membungkam pikirannya untuk
selamanya.
Kuda betina milik Sada berusaha bangkit
dan berderap kembali ke Maya sambil
meringkik keras. Kedua kuda betina itu
mudah gugup, dan sudah berlari kencang,
meski kelelahan. Dengan sifat Otori-nya,
Maya memikirkan kedua kuda itu; ia tidak
boleh membiarkan keduanya kabur. Ia
membungkuk dan diraihnya tali kekang kuda
Sada yang terayun-ayun. Tapi ia tidak tahu
apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Sekujur tubuhnya gemetar, begitu pula
kedua kuda itu; dan tak bisa memalingkan
pandangannya dari tiga mayat yang ter-
geletak di jalan. Si kuda, Ryume, agak lebih
jauh darinya, kemudian Sada dan Taku mati
dalam keadaan berangkulan.
Maya menggerakkan kudanya meng-
hampiri mereka, turun lalu berlutut di
sampingnya, menyentuh dan memanggil-
manggil nama mereka.
Bola mata Sada berdenyut: dia masih
hidup.
Luapan kepedihan di hatinya membuat
Maya hampir tercekik tak bisa bernapas. Ia
harus membuka mulut lalu menjerit, "Sada!"
Seolah menjawab jeritannya, tiba-tiba
muncul dua orang tepat di belakang Ryume.
Maya tahu kalau ia harus menggunakan
kemampuan menghilang atau bentuk kucing
lalu lari ke dalam hutan: ia berasal dari Tribe;
seharusnya bisa mengelabui siapa Saja. Tapi
badannya terasa lumpuh karena terguncang
dan sedih, ditambah lagi, ia tak ingin hidip
di dunia yang kejam ini, dunia yang mem-
biarkan Taku mati di bawah langit biru dan
matahari yang cerah.
Maya berdiri di antara kedua kuda betina,
memegangi tali kekang keduanya. Kedua
laki-laki itu datang menghampiri. Maya
hampir tidak bisa melihat mereka di malam
sebelumnya, di bawah remangnya pe-
nerangan di penginapan, tapi ia segera
mengenalinya. Kedua orang memegang
senjata, Akio membawa pedang dan pisau,
Hisao memegang senjata api. Mereka berasal
dari Tribe: mereka takkan membiarkannya
hidup hanya karena ia masih kecil.
Setidaknya aku harus bertarung, pikirnya, tapi
bodohnya, ia tak ingin melepaskan kedua
kuda betina itu.
Bocah itu menatapnya, mengacungkan
senjata api ke arahnya, sementara laki-laki
yang satu lagi membalik kedua mayat. Sada
mergerang pelan. Akio berlutut, mengambil
pisau dengan tangan kanan lalu menggorok
leher Sada dengan cepat. Ia meludahi wajah
Taku yang damai.
"Kematian Kotaro hampir terbalas,"
ujarnya. "Kedua Muto ini sudah membayar-
nya. Kini tinggal Si Anjing."
Bocah itu berkata, "Tapi ini siapa. Ayah?"
Suaranya terdengar kebingungan, seolah
pernah mengenal gadis itu.
"Bocah pengurus kuda?" sahut laki-laki
itu. "Sial sekali nasibnya!"
Akio berjalan menghampirinya dan Maya
mencoba menatap matanya, tapi laki-laki itu
tak berbalik menatapnya. Ketakutan yang
amat sangat mencekam Maya. Ia tak boleh
membiarkan laki-laki itu menangkapnya. Ia
hanya ingin mati. Dijatuhkannya tali kekang
kedua kuda, dan karena terkejut, kedua kuda
itu bergerak mundur. Maya menarik pisau
dari sabuknya lalu menaikkan tangannya
untuk menancapkan pisau itu di lehernya.
Akio bergerak lebih cepat dari gerakan
manusia mana pun yang pernah Maya lihat,
bahkan lebih cepat dibanding malam
sebelumnya, lalu mencengkeram pergelangan
tangan Maya. Pisaunya terjatuh seolah Akio
membelokkannya.
"Tapi bocah pengurus kuda macam apa
yang berusaha menggorok lehernya sendiri?"
tanyanya dengan sinis. "Seperti seorang
ksatria perempuan?"
Memegang Maya dengan tangannya yang
sekuat baja, Akio lalu menarik pakaiannya
dan menyelusupkan tangan satunya ke
selangkangan Maya. Gadis itu menjerit dan
meronta-ronta sewaktu Akio berusaha
membuka telapak tangannya. Akio ter-
senyum ketika dilihatnya garis lurus
melintang di telapak tangan gadis itu.
"Jadi!" serunya. "Sekarang kita tahu siapa
yang memata-matai kita semalam."
Maya mengira hidupnya sudah berakhir.
Tapi laki-laki itu melanjutkan, "Ini putri si
Anjing, salah satu dari si kembar: dia ada
tanda Kikuta. Gadis ini akan berguna. Jadi
kita biarkan dia hidup untuk saat ini."
Didekatinya Maya. "Kau kenal siapa aku?"
Maya tak mau menjawab.
"Aku Kikuta Akio, ketua keluargamu. Ini
putraku, Hisao."
Maya sudah mengenalnya, karena wajah-
nya sama seperti yang ia lihat dalam
mimpinya.
"Benar aku Otori Maya," sahutnya. "Ada
lagi, aku adalah adikmu...."
Maya ingin mengatakan lebih banyak lagi,
tapi Akio memindahkan cengkeramannya ke
leher, meraba bagian urat nadi, lalu menekan
hingga Maya tak sadarkan diri.*
Shigeko sering berlayar antara Hagi dan
Hofu, tapi belum pernah berlayar lebih ke
timur, di sepanjang pantai yang dilindungi
Laut Kitaran sampai Akashi. Cuaca cerah,
udara terasa sangat segar, angin laut ber-
hembus lembut dari selatan namun cukup
kencang untuk memenuhi layar dan mem-
buat kapal meluncur cepat. Dari berbagai
arah, pulau-pulau kecil bermunculan dari
permukaan laut, lereng-lerengnya kehijauan
tua dengan pepohonan cedar, buih
gelombang menghiasi pantainya. Dilihatnya
gerbang biara merah tua berkilauan di bawah
sinar matahari musim semi, kuil-kuil ber-
atapkan pohon runjung, dinding putih yang
mencuat dari kastil ksatria.
Tidak seperti Maya, Shigeko tidak pernah
mabuk laut, bahkan dalam perjalanan yang
paling sulit antara Hagi dan Maruyama,
ketika angin dari timur laut berpacu me-
lintasi laut keabu-abuan. Berlayar membuat
Shigeko gembira, bau air laut, tali temali dan
tiang kapal, bunyi kele-pak layar, kecipak air
laut dan keriat-keriut kayu, nyanyian
lambung kapal saat membelah lautan.
Muatan kapal dipenuhi berbagai macam
hadiah, termasuk pelana dan sanggurdi ber-
hias indah untuk Shigeko dan Hiroshi, serta
jubah resmi yang kesemuanya baru dibordir,
dicelup dan dilukis oleh perajin paling andal
dari Hagi dan Maruyama. Tapi hadiah yang
terpenting berdiri di atas dek; di bawah
naungan jerami: kuda-kuda yang dibiakkan
di Maruyama, masing-masing diikat dengan
dua utas tali di kepala dan ikat pinggang di
bawah perut; serta kirin, diikat dengan tali
dari sutra merah. Shigeko menghabiskan
banyak waktu dalam sehari di samping
hewan-hewan itu. Ia bangga akan kesehatan
dan ketampanan mereka karena ia sendiri
yang membesarkan hewan-hewan itu: dua
kuda berkulit belang, satu berwarna terang,
dan satu lagi berwarna merah bata. Semua
hewan itu kelihatan senang ditemani gadis
itu, dan mengikuti dengan pandangan mata
saat Shigeko berjalan di sekitar dek. Tak ada
rasa sesal akan berpisah karena mereka akan
diperlakukan dengan baik. Mungkin hewan-
hewan itu takkan melupakannya namun juga
takkan merindukan dirinya. Shigeko hanya
mencemaskan kirin yang tidak memiliki
pembawaan santai layaknya kuda. "Aku
khawatir kirin akan ketakutan ketika
berpisah dari kita, dan semua kawannya,"
katanya pada Hiroshi saat senja di hari ketiga
perjalanan mereka dari Hofu. "Lihat, dia
terus berpaling ke arah rumah. Seperti
merindukan seseorang: Tenba, barangkali."
"Sedan tadi kuperhatikan dia berusaha
mendekatimu, saat kau di dekatnya," sahut
Hiroshi. Tentunya dia akan merindukanmu.
Aku terkejut kau bisa berpisah dengannya."
"Aku hanya menyalahkan diriku! Aku
yang menyarankannya. Kirin adalah hadiah
yang sempurna: bahkan sang Kaisar pun pasti
kagum dan tersanjung dengan hadiah ini.
Tapi aku berharap hewan itu terbuat dari
gading atau logam berharga, tanpa perasaan,
dan aku takkan merasa khawatir memikir-
kannya akan kesepian."
Hiroshi menatapnya lekat-lekat. "Lagipula,
dia hanya seekor hewan. Mungkin tidak
semenderita seperti yang kau bayangkan. Dia
akan dirawat dengan baik, diberi cukup
makan."
"Hewan memiliki perasaan yang dalam,"
hardik Shigeko.
"Tapi dia tidak memiliki perasaan yang
sama dengan manusia saat dipisahkan dari
mereka yang disayanginya."
Shigeko beradu pandang dengan Hiroshi;
gadis itu menahan tatapan Hiroshi selama
beberapa saat. Hiroshi yang berpaling lebih
dulu.
"Dan mungkin kirin itu takkan kesepian
di Miyako," kata Hiroshi dengan suara pelan,
"karena kau juga akan berada di sana."
Shigeko tahu maksud ucapan Hiroshi
karena dia hadir saat Lord Kono mengatakan
kalau istri Saga Hideki meninggal baru-baru
ini, kehilangan yang membuat bangsawan
yang paling berkuasa di Delapan Pulau bebas
untuk menikah.
"Bila kirin merupakan hadiah yang
sempurna bagi Kaisar," imbuhnya, "apa
hadiah yang lebih baik bagi jenderal Kaisar?"
Mendengar kegetiran dalam suara Hiroshi,
Shigeko merasa gundah. Ia sudah lama
menyadari kalau Hiroshi mencintainya
seperti ia mencintai laki-laki itu. Mereka
berdua tahu apa yang ada di benak masing-
masing. Mereka berdua dilatih dengan
Ajaran Houou, dan telah mencapai tahap
kesadaran serta kepekaan yang tinggi.
Shigeko memercayai Hiroshi sepenuhnya.
Namun seperti tak ada gunanya membicara-
kan perasaannya: ia akan menikahi orang
pilihan ayahnya. Terkadang ia bermimpi
ayahnya memilih Hiroshi, dan terjaga dalam
rasa bahagia. Terkadang ia bertanya-tanya
apa bisa memilih calonnya sendiri karena
kini ia penguasa Maruyama; terkadang ia
sadar kalau tak ingin mengecewakan ayah-
nya. Shigeko dibesarkan dengan ajaran keras
keluarga ksatria: ia tidak bisa mematah-
kannya begitu saja.
"Aku berharap tidak harus tinggal jauh
dari Tiga Negara," gumamnya. Kirin berdiri
begitu dekat hingga bisa dirasakan hangatnya
napas hewan itu di pipinya. "Kuakui, aku
cemas dengan semua tantangan yang me-
nantiku di ibukota. Aku berharap perjalanan
kita sudah berakhirtapi di sisi lain aku juga
tak ingin perjalanan ini berakhir."
"Kau tak menunjukkan kecemasan saat
bicara dengan Lord Kono tahun lalu,"
Hiroshi mengingatkan.
"Mudah untuk merasa percaya diri di
Maruyama, saat dikelilingi begitu banyak
orang yang mendukungkuterutama kau."
"Kau juga akan mendapatkan dukungan
itu di Miyako. Miyoshi Gemba juga akan
berada di sana."
"Guru-guruku yang terbaikkau dan
dia."
"Shigeko," kata Hiroshi, memanggil
dengan nama yang sering dilakukannya
ketika gadis itu masih kecil. "Jangan sampai
ada hal yang mengurangi konsentrasimu
selama penandingan itu. Kita semua harus
menyingkirkan keinginan pribadi untuk
membiarkan ajaran kedamaian menang."
"Bukan menyingkirkan," sahut Shigeko,
"tapi mengatasinya." Gadis itu terdiam, tidak
berani berkata apa-apa lagi. Lalu satu
kenangan melintas di benaknya: pertama kali
ia melihat sepasang houou sewaktu kedua
burung itu kembali ke hutan di sekitar
Terayama untuk bersarang di pohon
pauwlonia dan membesarkan anak-anaknya.
"Ada ikatan yang kuat di antara kita,"
ujarnya. "Aku telah mengenalmu sejak
kecilbahkan mungkin di kehidupan
sebelumnya. Bila aku memang harus me-
nikah dengan orang lain, ikatan itu jangan
pernah putus."
"Tidak akan, aku bersumpah. Busur di
tanganmu, namun roh houou yang akan
menuntun anak panahnya."
Shigeko tersenyum, yakin kalau pikiran
dan tujuan mereka berdua telah menyatu.
Kemudian, sewaktu matahari tenggelam di
ufuk barat, mereka berjalan ke bagian
belakang dek dan memulai latihan ritual
kuno yang mengalir melewati udara bak air,
namun mengubah otot dan urat daging
menjadi sekeras baja. Kilau sinar matahari
mewarnai layar, membuat lambang bangau
Otori menjadi keemasan; panji-panji
Maruyama berkibar di tali tiang kapal. Kapal
pun tampak bermandikan cahaya, seolah
burung suci itu telah bertengger di atasnya.
Langit di arah barat masih memancarkan
garis merah ketika di arah timur muncul
bulan purnama dari bulan keempat.*
Beberapa hari setelah bulan purnama, Takeo
meninggalkan Inuyama menuju wilayah
Timur. Kepergiannya dilepas dengan penuh
semangat oleh penduduk kota. Saat itu ada
perayaan musim semi, ketika bumi hidup
kembali, cairan dari dalam bumi mengalir ke
pepohonan dan ke dalam aliran darah semua
orang. Kota itu dikuasai rasa percaya diri
serta harapan karena Lord Otori bukan
hanya tengah mengunjungi Kaisartokoh
yang dianggap separuh mistis oleh rakyat
tapi dia juga meninggalkan seorang putra:
kesedihan yang disebabkan oleh si kembar
akhirnya tersingkir. Tiga Negara belum
pernah begitu sejahtera. Burung houou ber-
sarang di Terayama, Lord Otori akan meng-
hadiahkan kirin kepada Kaisar; semua
pertanda ini menegaskan apa yang dilihat
sebagian besar rakyat pada anak-anak mereka
yang montok dan sawah yang subur. Semua
ini merupakan bukti dari penguasa yang adil
dan memedulikan kesejahteraan rakyatnya.
Namun semua sorak sorai, tarian, bunga
dan umbul-umbul tak mampu menyingkir-
kan kegelisahan Takeo. Meskipun ia ber-
usaha menyembunyikannya, namun wajah
tanpa ekspresi yang kini menjadi kebiasaan-
nya. Kecemasannya yaitu tidak adanya kabar
dari Taku: apakah dia membelot atau sudah
mati. Kedua hal itu sama-sama musibah
baginya, dan di satu sisi lagi, bagaimana
dengan nasib Maya? Takeo ingin sekali
kembali dan mencari tahu sendiri, namun
perjalanan membawa dirinya makin jauh dari
kemungkinan menerima kabar. Setelah me-
mikirkan masak-masak, beberapa di antara-
nya diceritakannya pada Minoru, Takeo
memutuskan untuk meninggalkan Kuroda
bersaudara di Inuyama, mengatakan bahwa
mereka akan lebih berguna di sana, dan
bahwa mereka harus mengirim kurir secepat-
nya bila ada kabar dari Taku.
"Jun dan Shin tidak senang," lapor
Minoru. "Mereka bertanya kepadaku apa
yang telah mereka lakukan sehingga tidak
dipercaya oleh Lord Otori."
"Tidak ada keluarga Tribe di Miyako,"
sahut Takeo. "Sungguh, aku tidak mem-
butuhkan mereka di sana. Tapi kau tahu,
Minoru, kalau kepercayaanku pada mereka
telah terkikis: bukan karena kesalahan
mereka, hanya karena aku tahu kesetiaan
pertama mereka pasti pada Tribe."
"Kurasa Anda mestinya bisa lebih me-
mercayai mereka," sahut Minoru.
"Mungkin aku menyelamatkan mereka
dari pilihan yang menyakitkan, dan kelak
mereka akan berterima kasih padaku," sahut
Takeo ringan, tapi sebenamya dia me-
rindukan kedua pengawal Tribe tersebut,
merasa telanjang dan tidak terlindungi tanpa
mereka berdua.
Empat hari keluar dari Inuyama, mereka
berjalan melintasi Hinode, desa tempat
Takeo pernah beristirahat bersama Shigeru
pada pagi setelah lari dari kejaran prajurit
Iida Sadamu.
"Tempat kelahiranku berjarak satu hari
perjalanan dari sini," komentarnya pada
Gemba. "Aku tidak melewati jalan ini lagi
selama hampir delapan belas tahun. Aku
ingin tahu apakah desa itu masih ada. Di
sanalah Shigeru menyelamatkan aku."
Tempat adikku, Madaren, dilahirkan,
mengingatkan dirinya, tempat aku dibesarkan
sebagai orang Hidden.
"Aku bertanya pada diriku sendiri,
alangkah beraninya aku muncul di hadapan
Kaisar. Mereka semua akan membenciku
karena asal-usilku."
Takeo dan Gemba berkuda berdampingan
di jalur yang sempit, dan ia bicara pelan agar
tidak didengar orang lain. Gemba melihat
sekilas ke arahnya lalu menyahut, "Kau tahu
aku membawa semua dokumen yang mem-
buktikan keturunanmu dari Terayama:
bahwa Lord Shigemori adalah kakekmu, dan
pengangkatanmu oleh Shigeru sah menurut
hukumdan disetujui oleh klan. Tak ada
yang bisa mempertanyakan legitimasimu."
"Tapi Kaisar sudah mempertanyakannya
lebih dulu."
"Kau membawa pedang Otori, dan di-
berkati dengan semua pertanda persetujuan
Surga." Gemba tersenyum. "Kau mungkin
tidak menyadari kekaguman Shigeru saat
membawamu pulang: kau begitu mirip
Takeshi. Seperti keajaiban: Takeshi tinggal
cukup lama bersama kami sebelumnya.
Kakakku Kahri adalah sahabatnya. Rasanya
seperti kehilangan saudara laki-laki tercinta.
Namun kesedihan kami tidak ada artinya
dibandingkan dengan Lord Shigeru, dan itu
merupakan pukulan terakhir dari sekian
banyak peristiwa buruk yang menimpanya."
"Ya, Chiyo menceritakan kisah-kisah
kehilangannya. Hidupnya diliputi kesedihan
dan nasib buruk yang tidak layak diterima-
nya; namun Shigeru tidak menunjukkannya.
Aku ingat perkataannya di malam pertama
aku bertemu Kenji: Aku tidak diciptakan
untuk berputus asa. Sering aku memikirkan
kata-kata ini, dan tentang keberaniannya saat
kami berkuda ke Inuyama dalam pengawasan
Abe dan pasukannya."
"Kau harus mengatakan hal yang sama
pada dirimu: kau tidak diciptakan untuk
berputus asa."
Takeo berkata, "Seharusnya begitu, tapi
dengan begitu banyak yang telah terjadi
dalam hidupku, itu menjadi suatu kepura-
puraan."
Gemba tertawa. "Beruntunglah karena kau
memiliki sekian banyak keahlian. Jangan
remehkan dirimu sendiri. Sifatmu mungkin
lebih kelam dari Shigeru, tapi tak kalah
kuatnya. Lihatlah apa yang telah kau raih:
hampir enam belas tahun kedamaian. Kau
dan istrimu telah menyatukan semua pihak
yang bertikai di seluruh Tiga Negara; kau
menangani kesejahteraan negara dengan
keseimbangan yang sempurna. Putrimu men-
jadi tangan kananmu, istrimu mendukung
sepenuhnya di rumah. Percayalah pada
mereka. Kau akan membuat kalangan istana
Kaisar terkesan sesuai dengan kemampuan-
mu. Percayalah padaku." Gemba terdiam dan
setelah beberapa saat melanjutkan senandung
kesabarannya.
Kata-kata Gemba terasa lebih dari sekadar
menenangkan; kata-kata itu tidak menenang-
kan tapi justru membuat Takeo mampu
menguasainya, dan akhirnya bisa melaluinya.
Selagi tubuh dan pikiran penunggangnya
rileks, maka begitu pula dengan kudanya:
Tenba menundukkan leher dan mem-
perpanjang langkahnya seolah jarak yang
ditempuh tengah dilahapnya, hari demi hari.
Takeo merasa semua inderanya mulai
terjaga: pendengarannya menjadi sama peka-
nya saat ia berusia tujuh belas tahun; mata
dan tangan senimannya mulai bergerak lagi
dengan sendirinya. Saat mendiktekan surat di
malam hari pada Minoru, rasanya ingin
sekali mengambil kuas dari tangan juru-
tulisnya itu. Kadang Takeo memang melaku-
kannya dengan cara menopang tangan
kanannya yang cacat dengan tangan kiri serta
menjepit kuas dengan dua jarinya yang ter-
sisa, dibuatnya sketsa pemandangan yang ada
di benaknya selama berkuda di siang hari:
sekawanan gagak beterbangan di sela-sela
pepohonan cedar, barisan angsa di tebing
dengan bentuk yang aneh, seekor burung tila
dan bunga lonceng di bebatuan. Minoru
mengumpulkan sketsa-sketsa itu lalu
mengirimnya dengan surat-surat untuk
Kaede, dan Takeo teringat pada lukisan
burung tila yang pernah ia berikan pada
istrinya bertahun-tahun yang lalu di
Terayama. Tangan cacatnya selama ini telah
mencegahnya untuk melukis, namun belajar
untuk mengatasi kendala itu telah mengasah
bakat alaminya menjadi gaya lukisan yang
unik dan luar biasa.
Jalanan dari Inuyama menuju perbatasan
terawat baik dan cukup lebar untuk tiga
penunggang kuda berjalan berdampingan.
Permukaan jalan rata karena Miyoshi Kahei
dan pasukannya melewati jalan ini beberapa
minggu sebelumnya. Pasukan garda depan
itu terdiri dari seribu orang yang sebagian
besar berkuda. Kahei juga membawa per-
sediaan pangan di atas kuda beban dan
gerobak yang ditarik lembu. Sisanya akan
bergerak dari Inuyama dalam beberapa
minggu lagi. Daerah perbatasan berbukit-
bukit. Selain dari jalanan yang akan mereka
lalui, puncaknya tak bisa dilewati.
Menyiagakan pasukan yang begitu besar
selama musim panas membutuhkan banyak
sumber daya, dan banyak pasukan pejalan
kaki yang berasal dari desa-desa tempat
panen tidak bisa dilakukan tanpa tenaga
mereka di ladang.
Takeo dan rombongannya berjumpa
dengan Kahei di dataran tinggi tepat di
bawah jalur sempit. Saat itu udara masih
dingin, rumput tepercik bintik putih salju
terakhir, air sungai dan kolam membeku. Pos
perbatasan kecil dibangun di sini, meski
tidak banyak pengembara yang melakukan
perjalanan dari wilayah Timur melewati jalur
darat karena lebih memilih jalur laut melalui
Akashi. Gugusan Awan Tinggi menjadi
perbatasan alami yang selama bertahun-
tahun membuat Tiga Negara terlindungi,
terabaikan bagian negara yang lain, tidak
dikuasai atau dilindungi Kaisar.
Kemah yang dibangun tampak teratur dan
disiapkan dengan baik: kuda-kuda berada di
barisannya, pasukan dipersenjatai lengkap
serta terlatih. Dataran itu sudah diubah
dengan pagar penghalang yang didirikan
dengan formasi kepala anak panah di
sepanjang tepi dan gudang penyimpanan
dibangun dengan cepat untuk melindungi
persediaan makanan dari cuaca dan hewan.
"Ada cukup tempat di ujung dataran bagi
pasukan pemanah,'' tutur Kahei. "Tapi kita
juga memiliki cukup senjata api saat prajurit
pejalan kaki datang dari Inuyama untuk
mempertahankan jalan bermil-mil di
belakang kita, begitu pula dengan pedesaan
di sekitarnya. Kita akan mendirikan blokade.
Tapi jika mereka masuk ke daerah di
sekitarnya, kita akan gunakan kuda dan
pedang."
Ia menambahkan, "Apakah kita tahu
senjata apa yang mereka miliki?"
"Waktu mereka kurang dari setahun untuk
mendapatkan atau menempa senjata api serta
melatih pasukan untuk menggunakannya,"
sahut Takeo. "Kita lebih unggul dalam hal
itu. Kita juga memiliki pasukan pemanah:
senjata tidak bisa diandalkan saat hujan atau
angin. Aku berharap bisa mengirim pesan
padamu. Aku akan mencari tahu sebisanya
tapi aku harus kelihatan seperti mencari
kedamaian; aku tidak boleh memberi alasan
bagi mereka untuk menyerang. Semua
persiapan ini demi mempertahankan Tiga
Negara; kita tidak mengancam siapa pun di
luar perbatasan wilayah kita. Kau harus tetap
di dataran ini dalam posisi yang murni
bertahan. Kita jangan sampai memancing
Saga atau menantang Kaisar."
"Rasanya aneh melihat Kaisar dengan
mata kepala sendiri," komentar Kahei. "Aku
iri padamu: kami mendengar tentang Kaisar
sejak kami masih kecil; beliau adalah
keturunan dewa, kendati selama bertahun-
tahun aku tidak percaya kalau beliau
memang benar-benar ada."
"Klan Otori kabarnya adalah keluarga
Kaisar," sahut Gemba. "Karena ketika
Takeyoshi diberikan Jato, bayi dalam
kandungan salah seorang selir Kaisar juga
akan djodohkan dengannya." Gemba ter-
senyum pada Takeo. "Maka kau pun
memiliki darah yang sama."
*Agak tercampur setelah benahun-tahun,"
sahut Takeo dengan nada ringan. "Tapi
mungkin karena beliau adalah kerabatku
maka akan memandangku dengan sikap yang
bersahabat. Bertahun-tahun lalu Shigeru
mengatakan bahwa karena kelemahan sang
Kaisar sehingga orang seperti lida bisa
merajalela tanpa bisa diawasi. Maka sudah
menjadi kewajibanku untuk memperkuat
kedudukan Kaisar. Beliau adalah penguasa
Delapan Pulau." Takeo melayangkan
pandangan ke arah gugusan gunung yang
warnanya berubah menjadi ungu tua di
bawah cahaya malam. Langit tampak ber-
warna putih kebiruan, dan bintang-bintang
pertama mulai bermunculan. "Aku hanya
tahu scdikit tentang sisanya: bagaimana
pemerintahannya, apakah mereka sejahtera,
apakah rakyatnya bahagia. Semua ini harus
dicari tahudan dibicarakan."
"Dengan Saga Hideki-lah kau harus
bicarakan semua itu," sahut Gemba. "Karena
saat ini dialah yang mengendalikan dua
pertiga negara, termasuk Kaisar."
"Tapi kita tidak akan membiarkannya
mengendalikan Tiga Negara," seru Kahei.
Ketidaksetujuan Takeo tidak diperlihatkan
terang-terangan pada Kahei, tapi secara
pribadi, seperti biasa, ia telah memikirkan
tentang negaranya dan cara terbaik untuk
melindunginya. Takeo sudah menyaksikan
kehancuran dan kehilangan korban manusia
akibat perang dan gempa. Ia tak ingin
menyerahkan negara yang telah makmur ini
pada Zenko, tapi juga tidak ingin melihatnya
terpecah belah dan berperang lagi. Ia tidak
percaya kalau Kaisar adalah dewa yang harus
disembah. Tapi ia menyadari pentingnya
kaisar sebagai simbol kesatuan, dan siap
untuk tunduk pada Kaisar demi mem-
pertahankan kedamaian dan meningkatkan
kesatuan seluruh negara.
Namun aku takkan menyerahkan Tiga
Negara kepada Zenko. Berulang kali dirinya
kembali lagi pada keyakinan ini. Aku takkan
melihatnya berkuasa menggantikan diriku.
Mereka menyeberangi jalur perbatasan saat
bulan menghilang, dan sebelum bulan penuh
lagi mereka hampir tiba di Sanda, kota kecil
yang berada di jalur antara Miyako dan
Akashi. Selagi menuruni lembah, sekaligus
memeriksa jalur pulang merekadan tempat
sepasukan kecil pasukan kemungkinan
berbelok dan menghadang musuh bila
diperlukanTakeo mempelajari keadaan
desa-desa, sistem pertanian, kesehatan anak-
anak, kerap berkuda keluar dari jalan
memasuki distrik di sekitarnya. Ia tercengang
menemukan bahwa ia tak dikenal penduduk
desa: reaksi mereka seolah kedatangan
pahlawan dari legenda yang mendadak
muncul di tengah-tengah mereka. Di malam
hari terdengar olehnya penyanyi buta
melantunkan lagi kisah Klan Otori: peng-
khianatan atas Shigeru dan kematiannya,
kejatuhan Inuyama, perang Asagawa,
mundur ke Katte Jinja serta pengambilalihan
kota Hagi. Ada juga nyanyian baru yang
digubah tentang kirin karena hewan itu
bersama putri Lord Otori yang cantik tengah
ditunggu di Sanda.
Daerah itu terbengkalai: Takeo terkejut
dengan rumah-rumah yang setengah runtuh,
sawah yang tidak digarap. Ia tahu dalam
perjalanan, dengan bertanya pada para
petani, bahwa temyata semua wilayah itu
bertempur habis-habisan melawan Saga
sebelum akhirnya menyerah dua tahun lalu.
Sejak itu pasukan bersenjata dan buruh yang
dibutuhkan telah melemahkan sumber daya
manusia desa-desa tersebut.
"Tapi setidaknya kini sudah damai, dan
kami berterima kasih pada Lord Saga," kata
salah seorang laki-laki yang lebih tua. Takeo
ingin tahu berapa banyak pengorbanan yang
mereka lakukan, dan masih ingin bertanya-
tanya lebih banyak lagi, tapi saat makin
mendekati kota ia bergabung lagi dengan
rombongannya dengan sikap yang lebih
formal. Banyak dari orang-orang itu
mengikutinya, berharap melihat kirin secara
langsung. Ketika tiba di Sanda, mereka
ditemani oleh sekerumunan besar orang, dan
makin bertambah ketika penduduk kota ber-
hamburan keluar untuk bertemu dengannya.
Mereka melambaikan umbul-umbul serta
rumbai-rumbai, menari dan menabuh
genderang. Sanda merupakan kota per-
dagangan dan tidak memiliki kastil atau
benteng. Masih tampak sisa-sisa kehancuran
akibat perang, tapi sebagian besar toko dan
rumah yang hangus terbakar sudah dibangun
kembali. Ada beberapa rumah penginapan
besar di dekat kuil; di jalan utama di depan
mereka, Takeo dipertemukan dengan
sekelompok kecil prajurit, membawa panji-
panji bergambarkan puncak gunung kembar
lambang Klan Saga.
"Lord Otori," ujar pemimpinnya, laki-laki
bertubuh besar dan gemuk yang meng-
ingatkan Takeo pada Abe, pengawal senior
Lord Iida. "Namaku Okuda Tadamasa. Ini
putra sulungku, Tadayoshi. Pemimpin kami
yang agung dan jenderal Kaisar meng-
ucapkan selamat datang kepada Anda. Kami
diutus untuk mendampingi Anda." Orang
itu bicara dengan bahasa resmi dan sopan.
Sebelum Takeo sempat menjawab, Tenba
meringkik lantang. Di atas atap laman di
penginapan muncul kirin dengan telinga
yang seperti kipas, kepala bermata besar di
atas leher panjang bercorak. Kerumunan
orang berseru kegirangan dengan serempak.
Mata dan hidung kirin tampak mencari-cari
sahabatnya. Ketika melihat Tenba, wajahnya
melembut seakan tersenyum; dan bagi
kerumunan itu, kirin seakan tersenyum pada
Lord Otori.
Bahkan Okuda pun tak mampu menahan
diri untuk meliriknya. Ekspresi kekaguman
melintas sesaat di wajahnya. Ototnya ber-
kerut tegang berusaha keras menahan diri,
matanya terbelalak. Putranya, pemuda ber-
usia kira-kira delapan tahun, terang-terangan
menyeringai.
"Aku berterima kasih pada Anda dan Lord
Saga," sahut Takeo tenang, mengabaikan
keheranan itu seolah kirin hanyalah hewan
peliharaan biasa. "Kuharap Anda bisa mem-
beri kehormatan dengan mengajakku dan
putriku makan malam bersama."
"Kurasa Lady Maruyama sudah menunggu
di dalam," sahut Okuda. "Aku terima
undangan Anda dengan senang hati."
Mereka semua turun dari kuda. Para
pengurus kuda berlarian menghampiri untuk
mengambil tali kekang. Pelayan bergegas
datang ke tepi beranda membawa baskom air
untuk mencuci kaki para tamu. Pemilik
penginapan pun muncul, seorang tokoh
penting dalam pemerintahan kota itu; dia
berkeringat karena gugup; membungkuk
rendah, kemudian bangkit, mengatur pelayan
dengan banyak instruksi dan tepukan tangan,
serta menggiring Takeo dan Gemba ke
kamar tamu utama.
Kamarnya cukup menyenangkan, meski-
pun tidak mewah. Alas lantainya masih baru
dan wangi, dan pintu-pintu bagian dalam
terbuka ke arah taman kecil yang berisikan
rumput dan sebongkah batu hitam yang
tidak biasa, seperti miniatur puncak kembar
gunung.
Takeo menatapnya, seraya mendengarkan
hiruk-pikuk kesibukan dalam penginapan di
sekelilingnya, suara bersemangat sang pemilik
penginapan. Kegiatan di dapur selagi makan
malam disiapkan, ringkikan Tenba dari istal,
dan terakhir suara putrinya, langkah kakinya
di luar. Takeo berbalik saat pintu bergeser
terbuka.
"Ayah! Aku sudah tak sabar ingin bertemu
ayah!"
"Shigeko," sahutnya, lalu dengan penuh
kasih sayang, "Lady Maruyama!"
Gemba yang sedari tadi duduk di beranda
sebelah dalam, kini berdiri dan menyerukan
kata yang sama. "Lady Maruyama!"
"Lord Miyoshi! Aku senang bertemu
Anda." "Hmm, hmm," sahutnya seraya ter-
senyum lebar dan bersenandung riang. "Kau
tampak baik."
Benar, pikir Takeo, putrinya bukan hanya
berada di puncak kecantikan masa mudanya,
tapi juga memancarkan kekuatan dan
kepercayaan diri seorang perempuan dewasa,
seorang penguasa.
"Dan Ayah lihai bawaanmu tiba dengan
sehat," ujar Takeo.
"Aku baru kembali dari kandang kirin.
Hewan itu senang bertemu dengan Tenba.
Agak mengharukan. Tapi apa Ayah baik-baik
saja? Perjalanan Ayah lebih berat. Ayah tidak
merasa kesakitan?"
"Ayah baik-baik saja," sahutnya. "Cuaca
hangat seperti ini rasa sakitnya masih bisa
diatasi. Gemba adalah teman seperjalanan
yang baik, dan kudamu itu luar biasa."
"Tidak ada kabar dari rumah?" tanya
Shigeko.
"Tidak ada, tapi karena Ayah tidak
menunggu kabar, maka ketenangan ini tidak
membuat Ayah cemas. Di mana Hiroshi?"
tanyanya.
"Dia sedang menengok keadaan kuda dan
kirin," sahut Shigeko dengan tenang.
"Bersama Sakai Masaki, yang ikut bersama
kami dari Maruyama."
Takeo mengamati putrinya yang tidak
menunjukkan emosi apa pun. Setelah
beberapa saat ia bertanya, "Ada pesan dari
Taku di Akashi?"
Shigeko menggeleng. "Hiroshi juga tengah
menunggu sesuatu, tapi tak satu pun orang
Muto di sana mendapat kabar darinya.
Mungkinkah terjadi sesuatu?"
"Aku tidak tahu; sudah lama tidak ada
kabar darinya."
"Aku bertemu dengannya dan Maya di
Hofu sebelum kami berangkat. Maya datang
untuk melihat kirin. Dia sehat, lebih mantap,
juga lebih bisa menerima anugerah bakatnya
dan lebih bisa mengendalikannya."
"Kau anggap kerasukan itu sebagai
anugerah?" seru Takeo, terkejut.
"Kelak akan begitu," sahut Gemba, lalu
dia dan Shigeko saling tersenyum.
"Jadi, katakan padaku para Guru Besar-
ku," ujar Takeo sinis, menyembunyikan
kekesalannya. "Mestikah aku mencemaskan
Taku dan Maya?"
"Karena kau tak bisa berbuat apa-apa dari
sini," Gemba menjelaskan, "maka tak ada
gunanya membuang energimu dengan
mengkhawatirkan mereka. Kabar buruk
cepat tersebar: kau akan mendengarnya
secepatnya."
Takeo menyadari kearifan kalimat ini, lalu
berusaha menyingkirkan masalah ini dari
benaknya. Tapi di malam-malam selanjut-
nya, selagi mereka melanjutkan perjalanan ke
ibukota, ia sering memimpikan kedua putri
kembarnya, dan di dunia lain yang berkabut
itu, disadarinya kalau mereka berdua tengah
menjalani semacam ujian berat yang aneh.
Maya berkilau bak emas, menarik semua
cahaya dari Miki yang dalam mimpinya
terlihat sehebat dan setajam sebilah pedang.
Sekali dia bermimpi mereka berdua sebagai
kucing dan bayangannya: ia memanggil-
manggil, tapi meskipun menengok, keduanya
bukan saja lidak melihat dirinya tapi juga
berlari menjauh dengan langkah tak ter-
dengar hingga berada di luar jangkauan
pendengaran dan perlindungannya. Takeo
terbangun dengan perasaan kehilangan yang
begitu menyakitkan kalau kedua putrinya itu
bukan anak-anak lagi. Bahkan bayi laki-
lakinya akhirnya akan tumbuh menjadi laki-
laki dewasa dan menantang dirinya; bahwa
orangtua membesarkan anak-anak hanya
untuk digantikan kedudukannya oleh
mereka, bahwa harga yang hams dibayar
untuk kehidupan adalah dengan kematian.
Malam terasa lebih pendek, dan saat
matahari makin bersinar cerah, Takeo
kembali dari dunia mimpi, mengumpulkan
kembali tekad dan kekuatannya untuk
melakukan tugas yang ada di hadapannya,
membingungkan lawan-lawannya dan me-
menangkan keberpihakan mereka, memper-
tahankan negara serta Klan Otori, di atas
segalanya, mencegah tejadinya perang.*
Perjalanan berlanjut tanpa insiden. Ini adalah
waktu yang paling tepat untuk melakukan
perjalanan. Siang kian panjang seiring makin
dekatnya waktu ketika matahari berada pada
jarak terjauh dari garis khatulistiwa. Okuda
nampak terkesanpada kirin, pada kuda
Maruyama, dan pada Shigeko yang memilih
untuk berkuda di sisi ayahnya; laki-laki itu
banyak bertanya pada Takeo tentang Tiga
Negara, perdagangan, administrasi, dan
kapal. Jawaban jujur Takeo membuat mata-
nya makin terbelalak.
Kabar tentang kedatangan kirin sudah
sampai mendahului mereka, dan sewaktu
mendekati ibukota, kerumunan orang
semakin banyak saat penduduk kota
berhamburan keluar untuk menyambut.
Mereka membuat hari itu sebagai hari libun
mereka mengajak istri dan anak dengan
mengenakan pakaian berwarna cerah,
menggetar tikar dan mendirikan payung
penahan sinar matahari warna merah tua
serta tenda putih, makan dan minum dengan
gembira. Takeo merasakan semua
kemeriahan ini sebagai pemberkatan atas per-
jalanannya, menyingkirkan pertanda buruk
dari eksekusi di Inuyama. Kesan ini di-
perkuat dengan Lord Kono yang mengirim
undangan untuk mengunjunginya pada
malam pertama di ibukota.
Kota itu dikelilingi tebing; danau besar di
bagian utara menyediakan kota itu dengan
air dan ikan. Dua sungai yang mengaliri kota
dihubungkan dengan beberapa jembatan
yang indah. Kota itu dibangun seperti kota
kuno di Shin: berbentuk persegi dengan jalan
lebar terbentang dari utara sampai ke selatan,
dengan jalanan yang lebih kecil bersaling-
silang. Istana kekaisaran terletak di ujung
jalanan utama, di sebelah biara agung.
Takeo serta rombongannya menginap di
kediaman yang tidak jauh dari tempat Kono.
Sebuah kandang dibangun dengan tergesa-
gesa untuk kirin. Takeo berpakaian dengan
ekstra hati-hati untuk menghadiri pertemuan
itu, lalu menaiki salah satu tandu mewah ber-
pernis yang diangkut dengan kapal laut dari
Hagi menuju Akashi. Hadiah-hadiah untuk
Kono dibawa oleh sebarisan pelayan: produk
Tiga Negara yang menjadi bukti kesejahteran
dan pemerintahan yang baik, apa saja yang
dinikmati atau dikagumi Kono selama di
wilayah Baratsalah satu hasil pengintaian
Taku.
"Lord Otori telah tiba di ibukota saat
matahari mendekati titik puncaknya," seru
Kono. "Waktu yang amat menguntungkan.
Aku berharap dengan amat sangat atas ke-
berhasilan Anda."
Ini orang yang membawa kabar bahwa
pemerintahanku ilegal dan Kaisar memintaku
agar turun takhta serta mengasingkan diri,
Takeo memperingatkan dirinya. Aku tidak
boleh terbuai pada sanjungannya. Takeo
tersenyum dan berterima kasih pada Kono,
lalu berkaia, "Semua ini ada di tangan Surga.
Aku akan tunduk pada kehendak Yang Mulia
Kaisar."
"Lord Saga ingin sekali bertemu Anda.
Apakah besok tidak terlalu cepat? Beliau
ingin menyelesaikan beberapa masalah se-
belum musim hujan mulai."
"Tentu saja." Takto bisa melihat tidak ada
gunanya menunda. Hujan pasti akan
menahan dirinya di ibukota sampai bulan
ketujuh: tiba-tiba dilihat dirinya sendiri kalah
dalam pertandingan itu. Lantas apa yang
harus ia lakukan? Bersembunyi di kota yang
lembap dan menjemukan ini sampai dirinya
bisa menyelinap pulang dan mengatur
pengasingan dirinya sendiri? Atau mencabut
nyawanya sendiri, meninggalkan Shigeko
sendirian di tangan Saga, di bawah
kekuasaannya? Apakah ia memang tengah
mempertaruhlan Tiga Negara, dirinya dan
putrinya, dalam sebuah pertandingan?
Takeo tak menunjukkan sedikit pun
kekhawatirannya, tapi justru menghabiskan
sisa malam itu dengan mengagumi koleksi
Kono dan membicarakan tentang lukisan
dengan orang tersebut.
"Sebagian di antaranya adalah milik
ayahku," tutur Kono ketika salah satu pen-
dampingnya membuka bungkusan sutra yang
berisi benda-benda berharga. "Tentu saja
sebagian besar koleksnya sudah hilang....
Tapi kita tidak perlu mengingat masa-masa
yang tidak menyenangkan itu. Aku minta
maaf. Aku pernah mendengar kalau Lord
Otori sendiri adalah seniman yang berbakat."
"Aku sama sekali tidak berbakat," sahut
Takeo. "Tapi melukis memberi kenikmatan
besar bagiku; meski aku tak sempat
melakukannya."
Kono tersenyum dan mengerutkan
bibirnya dengan sengaja.
Tak diragukan lagi dia pasti berpikir kalau
tak lama lagi aku ada waktu luang yang
banyak, renung Takeo, dan tak bisa menahan
diri untuk tersenyum juga pada ironinya
keadaan dirinya.
"Aku memberanikan diri untuk meminta
Anda memberikan salah satu karya Anda.
Dan Lord Saga pasti gembira kalau bisa
menerima satu juga."
"Kau berlebihan menyanjungku," sahut
Takeo. "Aku tidak membawanya. Beberapa
sketsa yang kubuat selama perjalanan sudah
kukirim pada istriku."
"Menyesal aku tidak bisa membujuk
Anda," seru Kono dengan hangat. "Menurut
pengalamanku, semakin jarang seniman
memamerkan karyanya, berarti semakin
besar bakatnya. Seperti harta terpendam, itu
justru lebih mengesankan dan lebih ber-
harga."
Kemudian dia melanjutkan dengan halus,
"Putri Anda tentunya merupakan harta Lord
Otori yang paling berharga. Dia akan
menemani Anda besok?"
Kedengarannya hanya sebagian dari
sebuah pertanyaan. Takeo agak memiringkan
kepala.
"Lord Saga amat menantikan bertemu
dengan lawannya," gumam Kono.
***
Lord Kono datang keesokan harinya bersama
Okuda, ayah dan anak, serta ksatria lain dari
kediaman Saga, untuk menjemput Takeo,
Shigeko, dan Gemba ke kediaman jenderal
itu. Sewaktu mereka turun dari tandu di
taman sebuah kediaman yang besar serta
megah, Kono bergumam, "Lord Saga
memintaku untuk menyampaikan per-
mintaan maafnya. Beliau sedang membangun
kastil barukelak akan ditunjukkannya pada
Anda. Untuk sementara, beliau khawatir
Anda merasa kalau kediamannya ini terlalu
sederhanatidak sebanding dengan yang
biasa Anda lihat di Hagi."
Takeo menaikkan alisnya dan melihat
sekilas ke wajah Kono, tapi tidak dilihat
adanya sindiran di sana.
"Kami mendapat keuntungan hidup
selama bertahun-tahun dalam kedamaian,"
sahut Takeo. "Kendati demikian, aku yakin
tak satu pun yang kami miliki di Tiga Negara
bisa dibandingkan dengan kemegahan
ibukota. Kalian pasti memiliki perajin paling
terampil, serta seniman yang paling
berbakat."
"Menurutku, orang-orang seperti itu
mencari lingkungan yang tenang agar bisa
menghasilkan karya seni mereka. Banyak
yang pergi dari ibukota dan baru sekarang-
sekarang ini mulai kembali. Lord Saga
memberi banyak komisi. Beliau sangat
mengagumi semua bentuk seni."
Minoru juga menemani mereka dengan
membawa gulungan berisi silsilah keluarga
dari semua yang datang dan daftar hadiah
untuk Lord Saga. Hiroshi memohon undur
diri, berdalih tak ingin meninggalkan kirin
tidak terjaga, meski Takeo menduga ada
alasan lain: kesadaran pemuda itu akan
kurangnya status dirinya, juga rasa enggan
bertemu laki-laki yang mungkin akan
dinikahi Shigeko.
Okuda, mengenakan pakaian formal
ketimbang baju zirah yang dia pakai
sebelumnya, membimbing mereka berjalan
menelusuri beranda yang lebar dan melewati
banyak ruangan yang masing-masing dihiasi
lukisan yang cemerlang, warna-warna cerah
berlatar berwarna emas. Takeo tak tahan
untuk tidak mengagumi ketegasan desain
dan kemahiran pembuatannya. Namun
dirasakannya semua lukisan itu dibuat untuk
memamerkan kekuatan dari penguasa:
semuanya berbicara tentang kemenangan;
tujuannya adalah untuk mendominasi.
Ada lukisan burung merak berjalan dengan
angkuh di bawah lebatnya pepohonan pinus.
Dua ekor singa mistis berjalan di sepanjang
dinding; naga dan harimau saling meng-
geram; elang menatap dengan berlagak
penting dari tempat yang memungkinkan
pandangan luas dan jelas di puncak tebing
kembar. Bahkan ada juga sepasang burung
houou sedang mematuk daun bambu.
Di ruangan terakhir inilah Okuda
meminta mereka menunggu, sementara dia
pergi bersama Kono. Takeo telah menduga
ini: ia pun kerap menggunakan tipu muslihat
yang sama. Tak seorang pun bisa dengan
mudah bertemu seorang penguasa. Takeo
menenangkan diri sambil memandang
lukisan burung houou. Ia yakin si seniman
belum pernah melihat burung itu, namun
melukisnya dari legenda. Dilayangkannya
pikirannya ke biara Terayama, ke hutan suci
pepohonan pawlonia di mana burung houou
tengah menetas. Di benaknya ia melihat
Makoto, sahabat karibnya yang mengabdikan
diri pada Ajaran Houou; ia merasakan
kekuatan spiritual sahabatnya itu dalam diri
kedua pendampingnya yang ada di dekatnya,
Gemba dan Shigeko. Mereka duduk tanpa
bicara, dan dirasakannya energi dalam
ruangan itu semakin menguat, memenuhi
dirinya dengan rasa percaya diri yang
mantap. Dipasang telinganya seperti yang
pernah dilakukanya di kastil Hagi ketika
dipaksa menunggu dengan cara yang sama;
di sana ia dengar pengkhianatan para paman
Shigeru. Kini ia dengar Kono berbicara pelan
pada seorang laki-laki yang diduganya adalah
Saga, tapi mereka hanya membicarakan hal-
hal yang biasa-biasa saja.
Kono sudah diperingatkan tentang pen-
dengaranku, pikirnya. Apa lagi yang telah
diungkap Zenko kepadanya?
Takeo mengenang masa lalunya yang
hanya diketahui oleh Tribe; seberapa banyak
yang Zenko tahu?
Beberapa saat kemudian Okuda datang
bersama seorang laki-laki yang diperkenal-
kannya sebagai kepala pelayan dan pengurus
administrasi Lord Saga. Orang itulah yang
akan mendampingi mereka ke ruang
pertemuan, menerima daftar hadiah yang
disiapkan Minoru serta mengawasi para
jurutulis yang mencatat acara yang akan ber-
langsung. Dia membungkuk sampai ke lantai
di hadapan Takeo dan berbicara dengan
sopan santun yang luar biasa.
Jalan lebar mengkilap membawa mereka
melewati taman kecil yang indah menuju ke
bangunan lainnya yang jauh lebih besar dan
lebih indah. Cuaca hari itu terasa semakin
hangat, dan gemericik air di kolam dan
tangki air memberi perasaan dingin. Takeo
bisa mendengar burung-burung di sangkar
berkicau di suatu tempat di kediaman ini,
dan menduga semua itu peliharaan Lady
Saga; lalu teringat kehilangan tragis yang
dialami Saga. Sesaat ia merasakan ketakutan
akan istrinya yang begitu jauh: bagaimana ia
bisa bertahan bila istrinya tiada? Bisakah ia
hidup tanpa istrinya? Menikah lagi demi
alasan negara?
Teringat lagi nasihat Gemba, disingkir-
kannya pikiran itu jauh-jauh, memusatkan
perhatiannya pada laki-laki yang akan
ditemuinya.
Kepala pelayan itu berlutut, menggeser
layar kasa agar terbuka dan menyembah
hingga kepalanya menyentuh lantai. Takeo
melangkah masuk dan membungkuk.
Gemba mengikutinya, tapi Shigeko
menunggu di ambang pintu. Hanya ketika
Takeo dan Gemba diminta duduk tegak,
barulah gadis itu masuk dengan gerakan
anggun dan menyembah di sebelah ayahnya.
Saga Hideki duduk di ujung ruangan.
Ruang kecil di sebelahnya terdapat lukisan
dengan gaya daerah daratan utama. Shin.
Mungkin itu lukisan bernama Genta Malam
Hari dari Biara di Kejauhan yang ter-
mahsyur, yang pernah Takeo dengar tapi
belum pernah dilihatnya. Dibandingkan
dengan ruangan lainnya, dekorasi ruangan
ini yang paling sederhana, seolah tak ada
yang boleh menyaingi kuatnya kehadiran
orang itu. Ternyata efeknya luar biasa, pikir
Takeo. Lukisan yang bersifat pamer hanya
menjadi pembungkus berhias: di sini hanya
pedang yang dipamerkan, tak perlu hiasan,
hanya baja tajam nan mematikan itu.
Semula Takeo mengira Saga adalah orang
yang brutal serta gegabah; kini ia mengubah
pendapatnya. Mungkin kejam, tapi tidak
gegabahdia laki-laki yang mengendalikan
pikiran sama ketatnya dengan mengendalian
tubuhnya. Tak diragukan lagi kalau ia meng-
hadapi lawan yang menakjubkan. Disesalinya
kekurangan dirinya, kurang terampil
memanah, dan kemudian mendengar setiap
senandung pelan dari sisi kirinya, tempat
Gemba duduk dengan sikap rileks. Dan tiba-
tiba dilihatnya kalau Saga takkan bisa di-
kalahkan dengan kekuatan, tapi justru
dengan kelembutan.
Shigeko tetap membungkuk dalam-dalam
sementara kedua orang itu saling menatap.
Usia Saga pasti beberapa tahun lebih tua dari
Takeo, mendekati empat puluh tahun,
dengan tubuh gemuk laki-laki separuh baya.
Namun orang itu memiliki keluwesan yang
tidak sesuai dengan usianya: duduk dengan
nyaman, gerakannya pun luwes. Memiliki
bahu bidang dan berotot ciri khas pemanah,
dan tampak lebih bidang karena sayap lebar
dari jubah resminya. Suaranya kasar, dengan
huruf konsonan diucapkan cepat, huruf
hidup diperpendek: ini pertama kalinya
Takeo mendengar aksen daerah timur laut,
tempat kelahiran Saga. Wajahnya lebar serta
bergaris tegas, bentuk matanya panjang dan
agak seperti bertudung, sementara yang me-
ngejutkan bentuk telinganya begitu halus,
hampir tanpa bagian bulat menonjol di
bagian bawahnya, begitu dekat dengan
kepalanya. Janggut dan kumisnya agak
panjang, keduanya agak beruban meski
rambutnya tidak beruban.
Pandangan mata Saga pun tak kalahnya
mengamati Takeo, berkedip memerhatikan
tubuhnya, berhenti sebentar saat melihat
tangan kanan bersarung tangan hitam.
Kemudian bangsawan itu mencondongkan
badan lalu berkata dengan kasar namun
ramah, "Bagaimana pendapat Anda?"
"Lord Saga?"
Saga memberi isyarat ke arah ruangan kecil
di sampingnya. "Tentu saja lukisan itu."
"Luar biasa. Karya Yu-Chien, benar?"
"Ha! Kono menyarankan aku meng-
gantungnya. Dia bilang Anda pasti
mengenalnya, dan bahwa lukisan ini lebih
menarik perhatian Anda ketimbang benda-
benda modern milikku. Bagaimana dengan
yang satu itu?"
Saga berdiri lalu berjalan ke dinding
sebelah timur. Kemari dan lihatlah."
Takeo bangkit lalu berdiri di sampingnya.
Tinggi mereka hampir sama, walau tubuh
Saga jauh lebih besar. Lukisan itu
menggambarkan pemandangan taman yang
dipenuhi bambu, plum dan pinus. Juga
dibuat dengan lima hitam, dilukis dengan
tenang serta menggugah.
"Ini juga sangat bagus," sahut Takeo
dengan kekaguman yang tulus. "Suatu maha
karya."
"Tiga kawan baik," ujar Saga, "luwes,
wangi serta kuat. Lady Maruyama, mari
bergabung bersama kami."
Shigeko berdiri lalu berjalan perlahan ke
sisi ayahnya.
"Ketiganya mampu menahan kerasnya
musim dingin," ujar Shigeko dengan suara
pelan.
"Memang," sahut Saga, kembali ke tempat
duduknya. "Aku melihat kombinasi itu di
sini." Dia memberi isyarat agar mereka men-
dekat. "Lady Maruyama adalah plum, sedang
Lord Miyoshi adalah pinusnya."
Gemba membungkuk hormat atas pujian
ini. "Kurasa aku bagian yang luwes," sahut
Takeo seraya tersenyum.
"Dari riwayat Anda, kurasa juga begitu.
Tapi bambu sangat sulit dibasmi bila
tumbuh di tempat yang salah."
"Bambu akan selalu tumbuh," ujar Takeo
setuju. "Lebih baik dibiarkan ditempatnya,
dan mengambil manfaat dari kegunaannya
yang banyak serta bervariasi."
"Ha!" Saga mengeluarkan tawa
kemenangan. Matanya menatap ke arah
Shigeko dengan ekspresi ingin tahu, per-
hitungan sekaligus hasrat. Kelihatannya dia
ingin bicara langsung pada gadis itu, namun
kemudian membatalkannya dan kembali
berbicara pada Takeo.
"Apakah filsafat ini menjelaskan alasan
Anda tidak menghadapi Arai?"
Takeo menjawab, "Bahkan tanaman
beracun pun bisa diambil manfaatnya, dalam
ilmu ketabiban, misalnya."
"Kudengar Anda tertarik dengan per-
tanian."
"Ayahku, Lord Shigeru, yang mengajariku
di bidang ini sebelum kematiannya. Bila
petani bahagia, maka negara akan menjadi
kaya dan stabil."
"Baiklah, aku tidak punya banyak waktu
untuk bertani beberapa tahun ini. Aku terlalu
disibukkan dengan peperangan. Tapi akibat-
nya kami kekurangan persediaan makanan di
musim dingin ini. Okuda mengatakan bahwa
Tiga Negara menghasilkan beras lebih
banyak dari yang bisa dikonsumsi."
"Kini banyak dari daerah di negara kami
yang mempraktikkan sistem panen ganda,"
tutur Takeo. "Memang benar, kami memiliki
banyak persediaan beras, begitu pula kacang
kedelai, gandum dan wijen. Kami diberkahi
panen yang baik selama bertahun-tahun,
serta terhindar dari kekeringan dan
kelaparan."
"Anda telah menghasilkan permata. Tak
heran begitu banyak orang yang mengincar-
nya dengan tamak."
Takeo agak memiringkan kepala. "Aku
pemimpin sah Klan Otori, dan menguasai
Tiga Negara secara sah menurut hukum.
Kekuasaanku adil dan direstui Surga. Aku tak
mengatakan semua ini untuk membual, tapi
untuk mengatakan bahwa sementara aku
mencari dukungan Anda, dan keberpihakan
Kaisarmemang, aku bersiap tunduk pada
Anda sebagai jenderal Kaisarharus dengan
persyaratan yang melindungi negara dan
pewarisku."
"Kita akan bicarakan itu nanti. Sekarang
mari makan dan minum."
Mengimbangi kesederhanaan ruangan itu,
makanannya pun lezat: hidangan musiman
ibukota yang tertata rapi, masing-masing
menawarkan pengalaman luar biasa bagi
mata yang memandang sena lidah yang
mengecap-nya. Sake juga dihidangkan, tapi
Takeo hanya minum sedikit, mengingat
perundingan bisa berlangsung hingga malam.
Okuda dan Kono bergabung dengan mereka
untuk santap siang, dan perbincangan
berlangsung dengan suasana riang. Mereka
hanya membicarakan lukisan, arsitektur,
keistimewaan Tiga Negara dibandingkan
yang ada di ibukota, yaitu puisi. Di
pengujung santap siang, Okuda, yang sudah
lebih mabuk ketimbang yang lainnya, meng-
ungkapkan lagi kekaguman bersemangatnya
pada kirin.
"Aku ingin sekali melihatnya dengan mata
kepalaku sendiri," ujar Saga, dan kelihatan
tanpa berpikir panjang berdiri. "Mari kita ke
sana sekarang. Siang ini cuaca cerah. Kita
akan lihat lapangan tempat pertandingan
kita." Digandengnya Takeo selagi berjalan
kembali ke pintu masuk utama dan berkata
dengan sikap penuh rahasia, "Dan aku harus
menemui juara-juara Anda. Lord Miyoshi
pasti salah satunya, kurasa, dan beberapa
ksatriamu yang lain."
"Yang kedua adalah Sugita Hiroshi.
Sedangkan yang ketiga Anda sudah bertemu.
Putriku, Lady Maruyama."
Cengkeraman tangan Saga mengencang
ketika berhenti; diputarnya tubuh Takeo agar
bisa menatap langsung wajahnya. "Memang
itu yang dilaporkan Lord Kono, tapi aku
mengira itu hanya lelucon." Orang itu
menatap Takeo dengan tajam. Lalu tertawa
dengan kasar, dan memelankan suaranya.
"Selama ini Anda memang berniat untuk
tunduk. Penandingan ini hanya formalitas
bagi Anda? Aku mengerti alasannya:
menyelamatkan mukamu."
"Aku tidak ingin menyesatkan anggapan
Anda," sahut Takeo. "Justru ini jauh dari
formalitas. Aku menganggapnya sangat
serius, begitu pula dengan putriku. Taruhan-
nya tidak bisa lebih tinggi lagi." Tapi bahkan
sewaktu bicara, keraguan berkecamuk dalam
dirinya. Ke mana kepercayaannya pada Guru
Besar Ajaran Houou membimbing dirinya?
Takut kalau Saga akan menganggap peng-
gantian dirinya dengan Shigeko sebagai
penghinaan dan penolakan untuk berunding.
Kendati demikian, setelah beberapa saat
diam karena terkejut, bangsawan itu tertawa
lagi. "Akan menjadi pertunjukan yang indah.
Lady Maruyama yang cantik melawan
bangsawan paling berkuasa di Delapan
Pulau." Saga tenawa kecil sewaktu
melepaskan tangan Takeo dan berjalan
menyusuri beranda, berseru dengan suara
lantang, "Bawakan busur dan anak panahku,
Okuda. Aku ingin memperlihatkannya pada
lawanku."
Mereka menunggu di bawah tepi atap
yang melengkung sementara Okuda pergi ke
tempat penyimpanan senjata. Orang itu
kembali dengan membawa busur yang
besamya lebih dari serentangan lengan dan
dilapisi pernis merah dan hitam. Seorang
pengawal mengikuti dengan membawa
tabung panah berisi serangkaian anak panah.
Anak panahnya tidak kalah mengesankan,
diikat dengan tali berlapis pernis emas; Saga
mengambil satu anak panah dari dalam
tabung lalu mengacungkannya untuk
diperlihatkan kepada mereka, anak panah itu
terbuat dari kayu pawlonia dengan ujung
tumpul, berbulu putih.
"Bulu burung bangau," ujar Saga, sambil
mengelus bulu-bulu itu dengan lembut lalu
melirik ke arah Takeo, yang sadar
sepenuhnya dengan lambang bangau Otori
di bagian belakang jubahnya.
"Kuharap Lord Otori tidak tersinggung.
Menurutku, bulu bangau menghasilkan
bidikan yang terbaik."
Diserahkannya kembali anak panah itu
pada pengawalnya lalu mengambil busur dari
tangan Okuda, mengulur dan meregangkan
dengan satu gerakan yang seperti tanpa
tenaga. "Kurasa busur ini hampir sama
tingginya dengan Lady Maruyama," ujarnya.
"Pemahkah Anda turut dalam perburuan
anjing?"
"Tidak, kami tidak berburu anjing di
wilayah Barat," sahut Shigeko.
"Itu olahraga yang hebat. Anjing-anjing
sangat bersemangat mengikutinya. Tentu saja
kami tidak membidik untuk membunuhnya.
Kau harus menyatakan bagian yang hendak
kau bidik. Aku ingin memburu singa atau
harimau. Itu akan menjadi buruan yang lebih
layak!"
"Bicara tentang harimau," lanjutnya
dengan karakternya yang sigap dan cepat,
seraya mengembalikan busur dan mengena-
kan sandalnya di anak tangga. "Kita harus
ingat untuk membicarakan tentang per-
dagangan. Anda mengirim kapal ke Shin dan
Tenjiku, bukan begitu?"
Takeo mengangguk patuh.
"Dan Anda telah kedatangan orang-orang
barbar dari selatan? Mereka amat menarik
bagi kami."
"Kami membawa hadiah-hadiah dari
Tenjiku, Silla, Shin serta Kepulauan Selatan
untuk Lord Saga dan Yang Mulia Kaisar,"
sahut Takeo.
"Hebat, hebat!"
Para pemanggul tandu beristirahat di
bawah tenda di luar gerbang. Mereka ber-
gegas berdiri lalu membungkuk hormat
sementara majikan mereka menaiki tandu,
tanpa kenyamanan, menuju penginapan yang
dijadikan tempat tinggal Otori. Panji-panji
bergambar bangau berkibar di atas gerbang
dan di sepanjang jalan. Bangunan utamanya
terletak di sebelah barat daerah berundak:
sebelah timur dibangun istal, tempat kuda-
kuda Maruyama menghentak kaki serta
mengibaskan kepala. Di depan istal ini, di
kandang beratap tiang bambu di satu sisi
dengan atap ilalang, berdirilah kirin, Di
sekeliling gerbang, telah berkumpul
sekerumunan orang yang berusaha melihat
kirin: anak-anak memanjat pohon, dan
seorang pemuda yang penuh inisiatif meng-
gunakan tangga.
Lord Saga satu-satunya orang di kelompok
itu yang belum pernah melihat makhluk
menakjubkan itu. Semua orang menatap
dengan pandangan gembira. Mereka tidak
kecewa. Bahkan Saga, dengan pengendalian
diri yang nyaris sempuma, tak kuasa
menahan tatapan penuh takjub di wajahnya.
"Hewan ini jauh lebih tinggi dari yang
kukira," serunya. "Pasti sangat kuat dan
cepat."
"Hewan ini justru sangat lembut," sahut
Shigeko seraya mendekati kirin. Saat itu
Hiroshi datang dari istal menuntun Tenba
yang tengah melompat dan berjingkrak di
ujung tali kekangnya.
"Lady Maruyama," seru Hiroshi. "Aku tak
menduga Anda kembali begitu cepat." Sesaat
keadaan sunyi senyap. Takeo perhatikan saat
Hiroshi melihat sekilas ke arah Saga lalu
wajahnya pucat. Kemudian pemuda itu
membungkuk hormat sebisa mungkin sambil
mengendalikan kuda, dan berkata dengan
canggung, "Tadi aku menunggang Tenba."
Kirin mulai melangkah dengan gembira
ketika melihat tiga makhluk yang paling
disayanginya.
"Aku akan mengembalikan Tenba bersama
kirin," ujar Hiroshi. "Kirin merindukannya.
Setelah berpisah kirin justru kelihatan
semakin terikat dengannya!"
Saga bicara seolah Hiroshi adalah
pengurus kuda. "Keluarkan kirin itu. Aku
ingin melihatnya lebih dekat."
"Tentu, tuan," sahut Hoiroshi dengan
membungkuk hormat lagi, rona merah
kembali merayapi leher dan pipinya.
"Kuda ini sangat tampan," komentar Saga
sewaktu Hiroshi mengikat Tenba pada tali
yang diregangkan dari masing-masing sisi
sudut dalam kandang. "Bersemangat. Dan
lumayan tinggi."
"Kami membawa banyak kuda dari
Maruyama sebagai hadiah," ujar Takeo
padanya. "Kuda-kuda itu dibiakkan serta
dibesarkan Lady Maruyama dan pengawal
seniornya, Lord Sugita Hiroshi." Sewaktu
Hiroshi menuntun kirin keluar dengan tali
sutra merah di tangan, Takeo menam-
bahkan, "Ini Sugita."
Saga mengangguk ke arah Hiroshi dengan
sikap asal-asalan: perhatiannya tersita habis
pada kirin. Tangannya menggapai dan
mengelus kulit bercorak coklat muda ke-
kuningan itu. "Lebih halus dari kulit
perempuan!" serunya. "Bayangkan kalau
kulit ini dihamparkan di lantai atau di
tempat tidur." Seolah sekonyong-konyong
tersadar dengan kesunyian yang merasa sakit
hati atas kata-katanya terse-but, dia meminta
maaf, "Hanya setelah hewan ini mati karena
usia tua, sewajarnya."
Kirin menjulurkan lehernya yang panjang
ke arah Shigeko dan dengan lembut
mengusap pipi gadis itu dengan hidung.
"Kulihat, kau adalah kesayangannya," ujar
Saga, memalingkan tatapan penuh
kekaguman Shigeko. "Kuucapkan selamat
pada Anda, Lord Otori. Kaisar akan ter-
pesona dengan hadiah Anda. Belum pernah
ada makhluk seperti ini di ibukota."
Kata-kata tadi diucapkan dengan murah
hati, tapi Takeo menduga ada nada iri dan
dengki di dalamnya. Setelah menginspeksi
kuda-kuda lebih jauh lagi, serta memper-
sembahkan dua kuda betina dan tiga kuda
jantan hitam kepada Lord Saga, mereka
kembali ke kediaman Saga. Bukan ke
ruangan sederhana sebelumnya, tapi ke aula
pertemuan yang didekorasi dengan megah,
tempat lukisan seekor naga terbang melintasi
dinding dan seekor harimau berkeliaran
mencari mangsa. Di sini Saga tidak duduk di
lantai, melainkan di kursi ukiran, mirip
Kaisar. Lebih banyak pengawalnya yang
menghadiri pertemuan tersebut; Takeo
menyadari keingintahuan mereka pada
dirinya dan terutama pada Shigeko. Tidak
biasa seorang perempuan duduk di tengah-
tengah laki-laki dalam acara seperti ini dan
turut berbicara tentang kebijakan. Takeo
merasa kalau mereka cenderung tersinggung
dengan pelanggaran adat semacam ini;
namun silsilah Klan Maruyama lebih tua
ketimbang Klan Saga dan klan wilayah
Timur lainnyasama tuanya dengan
keluarga kekaisaran yang merupakan
keturunan Dewi Matahari.
Pertama-tama mereka membicarakan
tentang upacara dalam acara perburuan
anjing, hari-hari jamuan dan ritual, arak-
arakan Kaisar; peraturan penandingan. Dua
lingkaran tali dipasang di atas tanah, satu tali
di dalam tali yang satunya lagi. Di setiap
babak enam anjing akan dilepas, satu demi
satu. Si pemanah berderap di sekeliling
lingkaran di tengah: nilai diberikan pada
bagian tubuh anjing yang dibidik. Permainan
itu merupakan permainan keterampilan,
bukan pembantaian: anjing yang terluka
parah atau mati dianggap tidak sah. Anjing
dipilih berbulu putih agar jika berdarah bisa
segera terlihat. Shigeko menanyakan satu
atau dua penanyaan teknis: lebar arena,
apakah ada ketentuan ukuran busur atau
anak panah. Saga menjawab dengan cepat,
dan dibumbui dengan kelakar sehingga
membuat para pengawalnya tersenyum.
"Dan sekarang kita bicara tentang hasil-
nya," ujarnya sopan. "Jika Lady Maruyama
menang, apa syarat Anda, Lord Otori?"
"Kaisar mengakui aku dan istriku sebagai
penguasa sah Tiga Negara; Anda mendukung
kami dan pewaris kami; Anda memerintah-
kan Arai Zenko tunduk pada kami. Sebagai
imbalannya, kami akan bersumpah setia pada
Anda dan Kaisar, demi kesatuan dan ke-
damaian Delapan Pulau; kami akan
menyediakan makanan, tenaga manusia sera
kuda untuk kampanye militer Anda
berikutnya, serta membuka pelabuhan kami
bagi kalian untuk perdagangan. Kedamaian
dan kesejahteraan Tiga Negara bergantung
pada sistem pemerintahan kami, dan ini
tidak boleh diubah."
"Terlepas dari hal terakhir ini yang ingin
kubicarakan dengan Anda lebih jauh lagi,
semuanya aku terima dengan baik," sahut
Saga, tersenyum dengan penuh percaya diri.
Dia tidak merasa terganggu dengan satu pun
syaratku karena memang dia tidak merasa
dirugikan, renung Takeo. "Dan apa syarat
Lord Saga?" tanyanya.
"Bahwa Anda segera mundur dari
kehidupan publik, dan menyerahkan Tiga
Negara pada Arai Zenko yang telah ber-
sumpah setia padaku dan juga pewaris sah
ayahnya Arai Daiichi; bahwa Anda boleh
mencabut nyawa Anda sendiri atau
mengasingkan diri ke Pulau Sado; bahwa
putra Anda harus dikirim padaku sebagai
tawanan; dan bahwa putri Anda harus
menikah denganku."
Kata-kata maupun nada suaranya seperti
menghina, dan kemarahan Takeo mulai
meluap. Dilihatnya ekspresi semua orang,
kepuasan dan kesenangan yang mereka
rasakan atas penghinaan terhadap dirinya.
Mengapa aku ke sini? Lebih baik mati
dalam perang ketimbang tunduk pada ial ini.
Takeo duduk tanpa bergerak, sadar kalau
tidak ada pilihan lain: setuju dengan usulan
Saga atau menolaknya, lari dari ibukota bak
penjahat dan bersiap, jika ia dan teman-
temannya hidup berhasil sampai di
perbatasan, untuk berperang.
"Menang atau kalah," Saga melanjutkan
bicaranya, "Kurasa Lady Maruyama pasti bisa
menjadi istri yang baik bagiku, dan aku
minta Anda pertimbangkan tawaranku."
"Aku turut berduka atas meninggalnya
istri Anda," sahut Takeo.
"Mendiang istriku orang yang baik: dia
memberiku empat anak yang sehat serta
merawat anakku yang lain; kurasa anakku
jumlahnya sepuluh atau dua belas. Kurasa
pernikahan antara keluarga kita bisa sangat
menguntungkan kedua belah pihak."
Semua rasa sakit hati yang pernah ia
rasakan ketika Kaede diculik kembali
menyapu dirinya. Sungguh keterlaluan kalau
ia mesti menyerahkan putri tercintanya pada
laki-laki kejam yang sudah tua ini, laki-laki
yang sudah memiliki beberapa selir, yang
takkan memperlakukan putrinya sebagai
penguasa atas haknya sendiri, yang hanya
ingin memiliki putrinya belaka. Namun
orang ini yang paling berkuasa di seluruh
Delapan Pulau; kehormatan dan manfaat
politis dari pernikahan ini besar sekali.
Tawaran itu telah diucapkan di depan orang
banyak: bila ia tolak secara langsung itu
berarti menghina.
Shigeko duduk dengan tatapan tertunduk,
tidak menunjukkan reaksinya pada pem-
bicaraan tersebut.
Takeo berkata, "Kehormatan ini terlalu
besar bagi kami. Putriku masih sangat muda,
tapi aku berterima kasih pada Anda dari
lubuk hatiku. Aku ingin bicarakan ini
dengan istrikuLord Saga mungkin belum
tahu kalau istriku turut menjalankan
pemerintahan Tiga Negara bersamakuaku
yakin, seperti halnya aku, istriku akan sangat
gembira dengan penyatuan antara kita."
"Semula aku ingin membiarkan istrimu
hidup, karena baru saja melahirkan, tapi bila
peran istrimu sama besarnya dengan dirimu
dalam pemerintahan, maka dia juga harus
diperlakukan sama seperti dirimu: kematian
atau pengasingan," sahut Saga dengan kesal.
"Andaikata Lady Maruyama menang, dia
boleh pulang untuk membicarakan hal ini
dengan ibunya."
Untuk pertama kalinya Shigeko angkat
bicara, "Aku juga memiliki syarat, jika aku
diperbolehkan bicara."
Saga melihat sekilas ke arah anak buahnya
lalu tersenyum dengan sabar. "Kami men-
dengarnya, nona."
"Aku minta Lord Saga untuk bersumpah
mempertahankan garis pewarisan keturunan
perempuan di Maruyama. Dan sebagai
pimpinan klan, aku bisa membuat pilihanku
sendiri dalam pernikahan, setelah ber-
konsultasi dengan para pengawal seniorku,
juga dengan ayah dan ibuku sebagai
atasanku. Aku sangatlah berterima kasih pada
Lord Saga atas kemurahan hatinya serta
kehormatan yang dianugerahkan pada diriku,
tapi aku tak bisa menerimanya tanpa
persetujuan dari klanku."
Shigeko bicara dengan tegas, sekaligus
dengan pesona yang kuat, hingga sulit bagi
siapa pun untuk merasa tersinggung. Saga
membungkuk hormat.
"Kulihat kalau aku punya lawan se-
banding," serunya, dan riak tawa melanda
anak buahnya.*
Bulan baru dari bulan keenam bergelayut di
langit sebelah timur di balik pagoda enam
lapis selagi mereka kembali ke kediaman.
Setelah mandi, Takeo meminta dipanggilkan
Hiroshi lalu menceritakan tentang pem-
bicaraan hari itu kepadanya, tidak keting-
galan satu pun, dan menutupnya dengan
usulan pernikahan.
Hiroshi hanya diam mendengarkan, hanya
mengatakan, 'Tentu saja ini tak terduga, dan
suatu kehormatan besar."
"Namun laki-laki seperti itu..." ujar Takeo
pelan. "Shigeko akan mengikuti saranmu,
juga saran aku dan istriku. Kita harus mem
pertimbangkan masa depannya sama
pentingnya dengan yang terbaik bagi Tiga
Negara. Kurasa hanya ada sedikit peluang
untuk memutuskan secepatnya." Takeo
menghela napas. "Begitu banyak yang
dipertaruhkan pada pertandingan inidan
semua orang di pihak Saga sudah memutus-
kan hasilnya!"
"Matsuda Shingen yang menyarankan
Anda untuk kemari, kan? Anda harus
memercayai penilaiannya."
"Ya harus datang, dan aku percaya pada-
nya. Tapi akankah Saga mematuhi
kesepakatannya? Dia orang yang tidak mau
kalah, dan begitu yakin akan menang."
"Seluruh kota terpukau dengan
kegembiraan pada Anda, Lady Shigeko, juga
kirin. Lukisan-lukisan bergambar kirin sudah
dijual, dan gambarnya ditenun menjadi kain
dan bordiran di jubah. Sewaktu Lady
Shigeko memenangkan lomba ini, dan
memang dia akan memenangkannya, Anda
akan didukungdan dilindungioleh
rakyat. Mereka bahkan telah menggubah
nyanyian tentang hal itu."
"Cinta rakyat adalah kisah tentang
kehilangan dan tragedi," sahut Takeo "Saat
aku di pengasingan di Pulau Sado, mereka
akan mendengar kisah melankolis tentang
diriku dan menangis, dan menikmatinya!"
Kemudian terdengar langkah ringan di
luar. Ketika pintu digeser terbuka, Shigeko
masuk diikuti Gemba yang membawa kotak
berpenis hitam dengan motif houou berlapis
emas. Saat melihat putrinya saling menatap
dengan Hiroshi dalam tatapan yang penuh
kasih sayang, membuat hati Takeo pedih
dengan penyesalan dan rasa iba. Mereka
sudah seperti pasangan suami istri, pikirnya,
terikat dengan ikatan yang kuat seperti itu.
Takeo berharap dapat memberikan putrinya
pada pemuda yang sangat dihormatinya ini,
yang setia sejak masih kecil, pemuda yang
pandai dan pemberani, dan sangat mencintai
putrinya. Namun semua ini tidak sebanding
dengan status dan kekuasaan yang dimiliki
Saga Hideki.
Gemba menyela renungannya. "Takeo,
kami mengira kau ingin melihat senjata-
senjata Lady Shigeko." Ditaruhnya kotak itu
di lama: dan Shigeko berlutut membukanya.
Takeo berkata dengan gelisah, "Kotaknya
kecil sekalipasti tidak bisa memuat busur
dan anak panah."
"Baiklah, memang ukurannya kecil," aku
Gemba. "Tapi Shigeko tidak terlalu tinggi:
dia harus memiliki sesuatu yang bisa
dipegang."
Shigeko mengeluarkan busur miniatur
yang indah, tabung anak panah, dan
kemudian anak panah, berujung tumpul
serta dengan bulu putih dan emas.
"Ini lelucon, kan?" ujar Takeo, jantungnya
berdebar ketakutan.
"Tidak, Ayah. Lihat, anak panahnya
dibului dengan bulu burung houou."
"Begitu banyak burung houou di musim
semi ini hingga kita bisa mengumpulkan
cukup bulu," jelas Gemba. "Mereka mem-
biarkan bulu-bulunya jatuh seolah mereka
menawarkannya."
"Mainan ini hampir tidak bisa menembak
burung gereja, apalagi anjing," sahut Takeo.
"Ayah tak ingin kami menyakiti anjingnya,
bukan begitu Ayah?" kata Shigeko seraya
tersenyum. "Kami tahu betapa sayangnya
Ayah pada anjing."
"Tapi ini perburuan anjing!" serunya.
"Tujuannya yaitu memanah anjing sebanyak
mungkin, lebih banyak dari Saga!"
"Anjing-anjing itu pasti bisa dipanah," ujar
Gemba. "Tapi dengan anak panah ini tidak
berbahaya dan tidak menyakiti anjing-anjing
itu."
Teringat cahaya api yang Gemba
lemparkan untuk membakar habis kekesalan
waktu itu, ia mencoba menekan kekesalan-
nya sekarang. "Tipuan sulap?"
"Lebih dari itu," sahut Gemba. "Kami
akan gunakan kekuatan Ajaran Houou:
keseimbangan antara laki-laki dan
perempuan. Selama keseimbangannya bisa
dipertahankan, maka kekuatannya tak ter-
kalahkan. Kekuatan ini yang menyatukan
Tiga Negara: kau dan istrimu merupakan
simbol hidup kekuatan itu; putrimu adalah
hasilnya, buktinya."
Gemba tersenyum yakin, seolah me-
mahami keberatan Takeo yang tak terucap.
"Kesejahteraan dan kebahagiaan yang kau
banggakan itu takkan terwujud tanpa
kekuatan itu. Lord Saga sama sekali tidak
mengenal kekuatan unsur perempuan, maka
dengan begitu dia akan dikalahkan."
"Ngomong-ngomong," kata Gemba
sewaktu mereka saling mengucapkan selamat
malam. "Jangan lupa menawarkan Jato
kepada Kaisar besok." Melihat tatapan Takeo
yang terkejut, dia lalu meneruskan, "Hal itu
sudah diminta dalam pesan pertama Kono,
kan?"
"Ya, memang, tapi begitu juga dengan
pengasingan diriku. Bagaimana kalau Kaisar
ingin menyimpannya?"
"Jato senantiasa menemukan pemiliknya
yang berhak, bukan begitu? Lagipula, kau
tidak menggunakannya lagi. Sudah waktunya
diserahkan."
Memang benar Takeo tak lagi meng-
gunakan pedang itu dalam pertempuran sejak
kehilangan jari-jarinya, tapi nyaris tak satu
hari pun berlalu tanpa dirinya menyandang
pedang itu. Ia juga cukup mahir meng-
gunakan tangan kiri untuk menopang tangan
kanannya, setidaknya dalam latihan per-
tarungan. Jato memiliki arti paling besar bagi
dirinya; pedang itu pemberian Shigeru dan
merupakan simbol nyata dari pemerintahan-
nya yang sah. Pikiran untuk melepaskannya
amat mengganggunya hingga ia merasa perlu
menghabiskan waktu beberapa lama untuk
bermeditasi, setelah berganti dengan pakaian
tidur.
Disuruhnya Minoru dan pelayannya pergi,
lalu ia duduk sendirian dalam ruangan yang
gelap, mendengarkan suara-suara malam dan
melambatkan napas dan pikirannya.
Nyanyian dan genderang bergema dari tepi
sungai, tempat penduduk kota menari-nari.
Katak berkuak di kolam taman, dan jangkrik
berderik di sela-sela semak. Perlahan-lahan
disadarinya kearifan dari saran Gemba: ia
akan mengembalikan Jato kepada Kaisar,
tempat pedang itu berasal.
***
Musik dan genderang terus terdengar hingga
larut malam, dan keesokan harinya jalanan
dipenuhi orang dewasa dan anak-anak yang
menari-nari. Mendengarkan suara mereka
saat ia bersiap menemui Kaisar, Takeo bukan
hanya mendengar nyanyian tentang kirin tapi
juga tentang burung houou:
Burung houou bersarang di Tiga Negara;
Lord Otori telah muncul di ibukota.
Kirin adalah hadiah bagi Kaisar;
Kuda-kudanya menggetarkan tanah kami
Selamat datang Lord Otori!
"Semalam aku keluar untuk melihat
suasana kota," ujar Hiroshi. "Aku men-
ceritakan pada satu atau dua orang lentang
bulu burung houou."
"Ternyata sangat efektif!" sahut Takeo,
menjulurkan tangan untuk mengambil jubah
sutra tebalnya.
"Rakyat menganggap kunjungan Anda
sebagai pertanda datangnya kedamaian."
Perasaan tenang yang telah dicapainya
semalam kian dalam. Diingatnya semua
pelatihannya, dari Shigeru dan Matsuda juga
dari Tribe. Takeo menjadi terasing dan tanpa
ekspresi; semua kegelisahan telah sirna dari
dirinya.
Para pendampingnya pun tampak dirasuki
kepercayaan diri yang sama. Takeo dibawa
dengan tandu berhias yang indah. Shigeko
dan Hiroshi menunggang kuda bersurai abu-
abu pucat, Ashige dan Keri, masing-masing
di kanan dan kiri kirin, keduanya memegangi
tali sutra merah tua yang terikat di kalung
berwarna emas berbentuk daun berlapiskan
kulit. Kirin berjalan dengan anggun tanpa
terganggu, memalingkan lehernya untuk
melihat kerumunan yang tengah mengagumi
dirinya. Teriakan dan seruan tidak mem-
pengaruhi ketenangan dirinya maupun pen-
dampingnya.
Kaisar telah melakukan perjalanan singkat
dari Istana Kekaisaran menuju Biara Agung
dengan kereta megah berpernis yang ditarik
sapi jantan hitam. Ada banyak lagi kereta
yang membawa bangsawan laki-laki dan
perempuan. Bangunan biara berwarna merah
cerah, baru dipugar dan dicat ulang. Di
depan bagian dalam gerbang, terdapat satu
arena yang luas, lingkaran-lingkaran yang
memiliki titik pusat telah diiandai dengan
warna-warna kontras, tempat perlombaan
akan diadakan. Para pemanggul tandu
berderap melintasi lingkaran ini, diikuti
rombongan Takeo. Para penjaga dengan
ramah menghadang kerumunan tapi mem-
biarkan gerbang sebelah luar tetap terbuka.
Pohon pinus berderet di bagian sampingnya,
dan di bawahnya gerai kayu dan tenda serta
anjungan sutra didirikan bagi para penonton,
dan ratusan bendera dan umbul-umbul
berkibar ditiup angin. Banyak orang, ksatria
dan bangsawan, sudah duduk di sini meski
perburuan anjing baru dimulai besok,
memanfaatkan tempat menonton yang
sangat bagus ini untuk melihat kirin. Para
perempuan herambut hitam panjang,
sedangkan laki-laki mengenakan topi resmi
kecil, membawa bantal sutra dan payung
pelindung sinar matahari, makanan dalam
kotak-kotak berpernis. Di gerbang berikut-
nya tandu diturunkan dan Takeo melangkah
keluar. Shigeko dan Hiroshi turun dari kuda;
Hiroshi mengambil tali kekang dan Takeo
berjalan dengan putrinya serta kirin menuju
bangunan utama biara.
Dinding putih dan balok merah ber-
kilauan diterpa sinar matahari siang. Saga
Hideki dan Lord Kono telah menanti dengan
pelayan di atas anak tangga. Semua pelayan
itu mengenakan jubah resmi yang sangat
mewah, lubah Saga berhiaskan kura-kura dan
burung jenjang,
Sedangkan jubah Kono berhiaskan bunga
peoni dan burung merak. Semuanya saling
bertukar hormat dan sopan santun, lalu Lord
Saga membimbing Takeo ke dalam, menuju
aula remang-remang yang disinari ratusan
lentera. Di bagian atas ruangan itu terdapat
mimbar berundak, di belakang tirai halus
dari bambu yang melindunginya dari mata
fana dunia, duduklah sang Kaisar, bagian
dari dewa-dewa.
Takeo menyembah, mencium aroma asap
minyak, keringat Saga tertutup oleh aroma
dupa wangi, dan aroma wewangian pelayan
Kaisar, Menteri Kanan dan Menteri Kiri
duduk di anak tangga di bawah penguasa
mereka.
Ini sama seperti yang ia harapkan, diterima
Kaisar, anggota pertama Klan Otori yang
dihormati sejak Takeyoshi yang legendaris.
Saga mengumumkan dengan suara yang
jelas namun sopan, "Lord Otori datang dari
Tiga Negara untuk mempersembahkan
hadiah yang indah bagi Paduka Yang Mulia,
serta meyakinkan Paduka Yang Mulia akan
kesetiaannya."
Kata-kata ini diulang salah satu Menteri
yang duduk di anak tangga mimbar tertinggi
dengan suara bernada tinggi dengan banyak
tambahan bahasa yang halus serta sopan
santun kuno. Ketika dia selesai bicara, semua
orang membungkuk hormat lagi, dan sesaat
kesunyian melanda. Takeo merasa diamati
Kaisar dengan seksama dari sela-sela celah
tirai bambu.
Kemudian dari balik tirai sang Kaisar
bicara, dengan suara yang tak lebih dari
sekadar bisikan.
"Selamat datang, Lord Otori. Kami sangat
senang menerima kedatanganmu. Kami tahu
ikatan lama yang ada di antara keluarga kita."
Takeo mendengar semua ini diucapkan
ulang oleh sang Menteri, dan ia bisa meng-
gerakkan sedikit posisinya untuk mengamati
reaksi Saga. Ia seperti mendengar tarikan
napas pelan dari laki-laki di sebelahnya. Kata-
kata Kaisar singkatnamun lebih dari yang
diharapkan: pengakuan atas hubungan Klan
Otori. Sungguh kehormatan yang amat besar
dan tak terduga.
Takeo memberanikan diri berkata,
"Bolehkah hamba bicara kepada Paduka
Yang Mulia?"
Permintaan itu diulang, dan ijin Kaisar
diucapkan ulang.
Takeo berkata, "Berabad-abad lampau
nenek moyang Paduka Yang Mulia mem-
berikan pedang ini, Jato, kepada Otori
Takeyoshi. Pedang ini diserahkan kepada
hamba oleh ayah hamba, Shigeru, sebelum
kematiannya. Hamba diminta mengembali-
kannya kepada Yang Mulia, dan kini hamba
dengan rendah hati melaksanakannya,
menawarkannya kepada Paduka sebagai
tanda kesetiaan dan pengabdian hamba."
Menteri Sebelah Kanan berunding dengan
Kaisar, lalu bicara lagi kepada Takeo.
"Kami menerima pedangmu dan peng-
abdianmu."
Takeo maju dengan tutut, lalu mengambil
pedang itu dari sabuknya. Rasa menyesal
menghunjam selagi ia menyodorkan pedang
itu dengan dua tangan.
Selamat tinggal, ujarnya pelan dalam hati.
Para menteri yang berada di undakan
paling rendah mengambil Jato dan
mengoperkannya dari satu petugas ke petugas
lainnya hingga sampai ke tangan Menteri
Kiri yang kemudian meletakkannya di depan
tirai.
Jato akan bicara; Jato akan kembali padaku,
pikir Takeo, namun Jato hanya tergeletak di
lantai, diam dan tak bergerak.
Kaisar bicara lagi, dan Takeo mendengar
kalau itu bukan suara dewa atau bahkan
bukan suara penguasa besar, tapi suara
manusia biasa yang penuh keingintahuan.
"Aku ingin melihat kirin dengan mataku
sendiri." Terjadi kegemparan mendadak
karena tak seorang pun yakin akan cara tepat
apa yang harus dilakukan. Kemudian Kaisar
melangkah keluar dari balik lirai serta
menjulurkan tangan kepada para pelayannya
untuk menuntunnya menuruni anak tangga.
Kaisar mengenakar jubah emas dengan
bordiran naga merah tua melintang di
punggung dan lengannya; hiasan itu
menambah tinggi badannya, tapi penilaian
Takeo sebelumnya ternyata benar. Di balik
megahnya pakaian yang dikenakannya,
berdiri seorang laki-laki berperawakan agak
pendek berusia kira-kira dua puluh delapan
tahun; pipinya tembam, mulutnya kecil dan
tegas, menunjukkan kecerdasan; matanya
berkilat dengan harapan.
"Biarkan Lord Otori ikut denganku,"
ujarnya sewaktu berjalan melewati Takeo,
dan Takeo pun mengikutinya, berjalan
dengan lutut.
Shigeko menunggu di luar bersama kirin.
Gadis itu berlutut dengan satu kaki ketika
Kaisar mendekat, dan dengan kepala ter-
tunduk memegangi tali, dia berkata, "Paduka
Yang Mulia: hewan ini tak sebanding dengan
keagungan Paduka Yang Mulia, namun kami
menawarkannya dengan harapan Paduka
Yang Mulia akan melihat dan mengakui
bawahan Paduka di Tiga Negara."
Ekspersi Kaisar merupakan salah satu
kekaguman yang murni, mungkin sama
kagumnya karena diajak bicara seorang
perempuan dan saat melihat kirin.
Diambilnya tali itu dengan hati-hati,
menengok sekilas pada para pegawai tinggi
kekaisaran, mendongak melihat leher kirin
yang panjang dan kepalanya, lalu tertawa
gembira.
Shigeko berkata, "Paduka Yang Mulia bisa
menyentuhnya: hewan ini amatlah lembut,"
dan manusia setengah dewa itu menjulurkan
tangan lalu mengelus bulu halus hewan yang
menakjubkan itu.
Kaisar bergumam, ''Kirin hanya muncul
ketika sang penguasa diberkati Surga."
Shigeko menyahut dengan suara yang
sama pelannya, "Maka Paduka Yang Mulia
memang diberkati."
"Ini laki-laki atau perempuan?" tanya
Kaisar pada Saga yang datang menghampiri
dengan cara sama yang dilakukan Takeo,
berlutut, karena Shigeko bicara dengan
menggunakan bahasa seorang penguasa laki-
laki.
"Paduka Yang Mulia, ini putri Lord Otori,
Lady Maruyama."
"Dari tanah tempat perempuan berkuasa?
Lord Otori telah membawa banyak benda
yang eksotis! Semua yang kami dengar
tentang Tiga Negara memang benar adanya.
Alangkah inginnya aku berkunjung ke sana,
tapi mustahil aku meninggalkan ibukota."
Dielusnya lagi kirin. "Apa yang bisa
kuberikan sebagai imbalannya?" tanyanya.
"Aku sangsi kalau memiliki apa pun yang
sebanding." Kaisar berdiri seolah berpikir
keras selama beberapa saat, dan kemudian
berbalik dan menengok ke belakang seakan
tersengat oleh ilham yang datang tiba-tiba.
"Bawakan padaku pedang Otori," serunya.
"Akan kuanugerahkan kepada Lady
Maruyama!"
Takeo ingat suara dari masa lalu: Pedang
itu akan berpindah dari satu tangan ke
tangan lainnya. Kenji. Pedang yang Kenji
serahkan kepada Shigeru setelah kekalahan
Otori di Yaegahara, dan kemudian dibawa
Yuki, putri Kenji, untuk Takeo, dan kini
diserahkan ke tangan Maruyama Shigeko
oleh Kaisar.
Takeo membungkuk hingga menyentuh
tanah lagi, dan selagi duduk legak, dilihatnya
Kaisar tengah mengamatinya dengan penuh
selidik. Pada saat itu, godaan akan kekuatan
mutlak berkilat di hadapannya. Siapa pun
yang disukai Kaisaratau, bisa diungkapkan
dengan kata yang lebih sederhana,
mengendalikan Kaisarmaka bisa mengen-
dalikan Delapan Pulau.
Itu bisa saja aku dan Kaede, pikirnya. Kami
bisa bersaing dengan Saga: jika kami
mengalahkannya besok dalam pertandingan,
kami bisa menggantikan kedudukannya.
Pasukan kami sudah siap. Aku bisa kirim kurir
kepada Kahei lebih awal. Kami akan
mendesaknya kembali ke utara dan ke arah
laut. Sagalah yang akan diasingkan, bukan
aku!
Takeo menghibur diri dengan khayalannya
selama beberapa saat, lalu menyingkirkannya
jauh-jauh. Ia tidak menginginkan Delapan
Pulau; ia hanya menginginkan Tiga Negara,
dan ingin agar negaranya tetap damai.
***
Sisa hari itu dihabiskan dengan jamuan
makan, pertunjukan musik dan drama,
kompetisi puisi, dan bahkan peragaan
permainan kegemaran para bangsawan muda,
yaitu bola sepak. Lord Kono membuktikan
diri sangat mahir dalam permainan ini.
"Perilakunya yang acuh tak acuh menyem-
bunyikan keahlian fisiknya," komentar
Takeo pelan kepada Gemba.
"Mereka akan menjadi lawan yang
sebanding," sahut Gemba setuju dengan
tenang.
Kemudian ada juga balapan kuda sebelum
matahari terbenam. Tim Lord Saga yang
menunggang kuda perang Maruyama
menang dengan mudah, menambah
kekaguman pengunjung kepada sang
jenderal, dan kegembiraan serta kekaguman
akan hadiah yang tiada bandingannya.
Takeo kembali ke kediaman dengan rasa
gembira dan bersemangat atas hasil hari ini,
meskipun masih cemas tentang esok hari. Ia
telah menyaksikan keahlian berkuda lawan.
Ia tak percaya kalau putrinya bisa menang.
Namun Gemba ternyata benar tentang
pedang itu. Seharusnya ia juga percaya
tentang hasil pertandingan itu.
Dinaikkannya tirai tandu yang terbuat dari
sutra untuk menikmati udara malam. Saat
ditandu melewati gerbang, dia melihat, dari
sudut matanya, garis bentuk tubuh ber-
bayang dari seseorang yang menggunakan
kemampuan menghilang. Ia terkejut karena
tidak menduga ada anggota Tribe beroperasi
di ibukota: tidak ada dalam catatannya,
maupun sepengetahuan keluarga Muto yang
pernah menyatakan kalau mereka telah
menembus sejauh ini sampai ke wilayah
Timur.
Secara naluri disentuhnya pedang, sadar
kalau ia tak bersenjata, percikan keingin-
tahuannya muncul lagi saat menghadapi
kekekalan hidupnyaapakah orang ini yang
akan berhasil membunuhnya, dan mem-
buktikan bahwa ramalan itu salah?saat
tandu belum menyentuh tanah ia sudah
turun. Dengan mengacuhkan para pelayan-
nya, ia berlari ke gerbang dan mencari-cari
dengan mata orang itu di antara kemmunan,
penasaran apakah tadi ia salah lihat.
Namanya dilantunkan banyak suara, tapi ia
seperti bisa membedakan satu orang yang
dikenalnya, lalu dilihatnya gadis itu.
Takeo segera mengenalinya sebagai
anggota Muto, tapi butuh waktu beberapa
saat untuk mengingat siapa gadis itu: Mai,
adik Sada, yang ditempatkan di kediaman
orang asing untuk mempelajari bahasa serta
memata-matai mereka.
"Mari cepat masuk," perintahnya pada
gadis itu. Begitu sudah di dalam, diperintah-
nya penjaga untuk menutup serta memalang
gerbang, kemudian berbalik lagi pada gadis
itu. Gadis itu kelihatan lelah dan kotor
karena perjalanan jauh.
"Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau
membawa kabar dari Taku? Apakah Jun
mengirimmu?"
"Aku harus bicara dengan Lord Otori
saja," bisiknya.
Melihat kesedihan di garis bibir dan dalam
tatapan matanya, jantungnya berdegup
kencang karena takut pada apa yang akan
disampaikan gadis itu.
"Tunggu di sini. Aku akan langsung
memanggilmu."
Takeo memanggil pelayan untuk mem-
bantunya mengganti jubah resminya. Setelah
menyuruh mereka menyajikan teh,
memanggil gadis itu lalu menyuruh mereka
pergi; bahkan putrinya, atau Lord Miyoshi
tak boleh masuk.
"Apa yang telah terjadi?"
"Lord Taku, dan kakakku sudah tiada,
tuanku."
Kabar itu menghantam dirinya bak
pukulan ke dadanya. Takeo menatap gadis
itu, tak bisa bicara, merasakan gelombang
kesedihan menggelegak hingga ke urat nadi-
nya; Takeo memberi isyarat agar gadis itu
melanjutkan.
"Mereka diduga diserang bandit di tempat
berjarak satu hari berkuda dari Hofu."
"Bandit?" tanyanya tak percaya. "Bandit
macam apa yang ada di Negara Tengah?"
"Itulah pernyataan resmi yang dikeluarkan
Zenko," sahut Mai. "Tapi Zenko sedang
melindungi Kikuta Akio. Desas-desus yang
beredar bahwa Akio dan putranya yang
bunuh Taku untuk balas dendam atas
kematian Kotaro. Sada tewas bersamanya."
"Dan putriku?" bisik Takeo, air mata
menggenang di pelupuk matanya dan hampir
menetes.
"Lord Otori, tidak ada yang tahu di mana
putri Anda. Mungkin putri Anda berhasil
lari, atau ditangkap Akio...."
"Ditangkap Akio?" ucapnya mengulang
perkataan itu.
"Mungkin dia melarikan diri," sahut Mai.
"Tapi dia belum ke Kagemura, atau
Terayama, atau tempat lainnya yang
diperkirakan sebagai tujuannya melarikan
diri."
"Apakah istriku tahu?"
"Aku tidak tahu, tuan."
Dilihatnya ada hal lain lagi, alasan lain
mengapa gadis mi menempuh perjalanan
sejauh ini, mungkin tanpa ijin dari Tribe,
dan tidak diketahui mereka, bahkan Shizuka.
"Ibu Taku pasti sudah diberitahu?"
"Sekali lagi, aku tak tahu. Sesuatu telah
terjadi dalam jaringan Muto, tuan. Pesan-
pesan salah sasaran, atau dihaca oleh orang
yang salah. Orang-orang mengatakan kalau
mereka ingin kembali ke masa silam, saat
Tribe memiliki kekuasaan yang sesungguh-
nya. Kikuta Akio sangat dekat dengan Zenko
dan banyak orang Muto menyetujui
persahabatan merekaorang-orang mengata-
kan mereka berdua seperti Kenji dan Kotaro
sebelum..."
"Sebelum aku datang," ujar Takeo
murung.
"Aku tidak berhak mengatakannya. Lord
Otori. Keluarga Muto bersumpah setia
kepada Anda, dan Taku serta Sada setia
kepada Anda. Itu sudah cukup bagiku. Aku
meninggalkan Hofu tanpa mengatakan pada
siapa pun, berharap bisa menyusul Lady
Shigeko dan Lord Hiroshi, tapi mereka
sudah beberapa hari di depanku. Aku terus
mengikuti hingga aku sadar sudah di
ibukota. Aku berjalan selama enam minggu."
"Aku sangat berterima kasih." Teringat
olehnya kalau gadis itu juga tengah bersedih.
"Dan aku sangat berduka atas kematian
kakakmu dalam melayani keluargaku."
Mata gadis berkilat diterpa sinar lentera,
namun tidak menangis.
"Mereka diserang dengan menggunakan
senjata api," tuturnya dengan nada sedih.
"Tak ada yang bisa membunuh mereka
dengan menggunakan senjata biasa. Taku
tertembak di leher; dia pasti mati kehabisan
darah, dan peluru itu menghantam Sada
setelah menembus kuda, tapi dia bukan mati
karena peluru: lehernya digorok."
"Akio punya senjata api? Darimana dia
dapat?"
"Dia sudah di Kumamoto selama musim
dingin. Senjata itu pasti pemberian Zenko;
mereka sudah melakukan perdagangan
dengan orang-orang asing."
Takeo duduk terdiam, teringat saat ia
mencengkeram leher Taku yang menyelinap
masuk ke kamarnya di Shuho: saat itu Taku
baru berumur sembilan atau sepuluh tahun.
Kenangan itu diikuti dengan kenangan
lainnya, hampir membuat ia terpuruk. Seraya
menutupi wajah dengan tangan, ia berusaha
sekuat tenaga untuk tidak menangis.
Kesedihannya disulut dengan kemarahannya
atas Zenko yang telah ia biarkan hidup hanya
untuk melihat orang itu bersekongkol mem-
bunuh adiknya.
"Lord Otori," ujar Mai ragu-ragu.
"Haruskah aku memanggil seseorang agar
menemui Anda?"
"Tidak!" sahutnya, seraya berusaha
mengendalikan diri, waktu untuk menjadi
lemah sudah berakhir. "Kau tak tahu situasi
kami di sini. Kau tidak boleh mengatakan ini
pada siapa-siapa. Jangan ada hal yang
mengganggu selama beberapa hari ke depan.
Akan ada pertandingan yang melibatkan
putriku dan Lord Hiroshi. Mereka tidak
boleh diganggu. Mereka tidak boleh tahu hal
ini hingga pertandingannya selesai. Tidak
seorang pun boleh tahu."
"Tapi Anda harus segera kembali ke Tiga
Negara! Zenko..."
"Aku akan kembali secepatnya, lebih awal
dari rencana. Tapi aku tak ingin
menyinggung tuan rumahLord Saga,
Kaisarmaupun membiarkan Saga
mencium pengkhianatan Zenko. Sementara
ini aku dalam posisi yang menguntungkan
tapi itu bisa berubah kapan saja. Begitu
lombanya selesai dan kami tahu hasilnya, aku
akan pamit. Meskipun beresiko terjebak
dalam hujan, namun hal ini tidak bisa
ditunda. Kau akan ikut dengan kami, tentu
saja; tapi untuk sementara waktu ini aku
memintamu untuk menjauh. Shigeko bisa
mengenalimu. Hanya dua hari. Nanti aku
akan ceritakan tentang kabar ini padanya dan
juga Hiroshi."
Takeo mengatur agar Mai diberi uang dan
dicarikan penginapan, lalu gadis itu pergi,
berjanji akan kembali dalam dua hari.
Mai baru saja pergi ketika Shigeko dan
Gemba datang. Sedari tadi mereka
memeriksa keadaan kuda, menyiapkan
pelana dan tali kekang untuk lomba besok,
serta membahas strategi. Shigeko, yang
biasanya pandai mengendalikan diri serta
tenang, kini gembira dengan kejadian hari
ini, dan tak sabar menanti penandingan. Ia
lega karena ini berarti putrinya takkan
memerhatikan sikap diam dan kurang
bersemangat dirinya, juga lega karena
gelapnya ruangan.
Shigeko berkata, "Aku kembalikan Jato
pada Ayah."
"Tidak boleh," sahutnya. "Kaisar yang
berikan padamu. Sekarang pedang itu
menjadi milikmu."
"Pedang ini terlalu panjang," protes
putrinya.
Takeo memaksakan diri untuk tersenyum.
"Kendati demikian, tetap saja itu milikmu."
"Akan kuberikan pada biara sampai...."
"Sampai apa?" Takeo memotong ucapan
putrinya.
"Sampai putra Ayah, atau putraku, cukup
dewasa untuk memilikinya."
"Bukan penama kalinya pedang itu berada
di biara," sahut Takeo. "Tapi pedang itu
milikmu, dan pedang juga memastikan
dirimu bukan hanya sebagai pewaris Klan
Maruyama, tapi juga Klan Otori."
Takeo menyadari bahkan saat ia bicara
bahwa pengakuan Kaisar membuat persoalan
pernikahan Shigeko justru makin penting.
Shigeko akan menyerahkan Tiga Negara
kepada orang yang menikahinya, suami yang
direstui Kaisar. Apa pun permintaan Saga, ia
takkan menyerah begitu saja, tidak sebelum
ia konsultasi dengan Kaede.
Takeo sangat merindukan Kaede saat ini,
bukan hanya menginginkan tubuhnya, tapi
kearifan, kejernihan pikiran, sena kekuatan-
nya yang lembut, aku tidak berarti tanpa dia,
pikirnya. Rasanya ingin sekali berada di
rumah.
Tak sulit untuk membujuk Shigeko
beristirahat lebih awal, dan Gemba juga pergi
tidur, meninggalkan Takeo sendirian meng-
hadapi malam yang panjang.*
Minoru datang, seperti biasa, saat matahari
baru terbit. Dia datang bersama para pelayan
perempuan yang membawa teh.
"Hari ini sepertinya akan menjadi hari
yang cerah," ujarnya. "Aku telah menyiapkan
catatan atas semua yang terjadi kemarin, dan
juga mencatat semua yang akan terjadi hari
ini."
Ketika Takeo mengambil catatan itu tanpa
menjawab, si jurutulis berkata dengan ragu,
"Lord Otori kelihatannya tidak sehat."
"Aku kurang tidur, itu saja. Aku sehat-
sehat saja, aku harus terus memesona serta
mengesankan. Aku tidak bisa bersikap
sebaliknya."
Minoru menaikkan alis sedikit, terkejut
dengan suara dingin Takeo.
"Tentunya kunjungan Anda sangat
berhasil, kan?"
"Kita akan tahu sore ini."
Takeo tiba-tiba memutuskan dan berkata,
"Aku akan mendiktekan sesuatu padamu.
Jangan berkomentar dan jangan beritahu
siapa-siapa. Kau harus mengatur kepulangan
kita agak lebih awal dari rencana."
Minoru menyiapkan batu tinta dan meng-
ambil kuas tanpa bicara. Tanpa memihak
Takeo menceritakan semua vang diceritakan
Mai semalam, dan Minoru menulisnya.
"Aku turut berduka cita," ujarnya ketika
Takeo selesai mendikte. Takeo memandang
Minoru dengan tatapan menuduh. "Aku
minta maaf atas kurang terampilnya diriku
ini. Tanganku gemetar dan tulisanku sangat
buruk."
"Tidak apa-apa, selama masih bisa dibaca.
Simpan baik-baik: aku akan memintamu
membacakannya, malam ini atau besok."
Minoru membungkuk hormat. Takeo
sadar akan simpati tanpa kata-kata dari
jurutulisnya; kenyataan bahwa ia telah
berbagi kabar kematian Taku mengurangi
penderitaannya.
"Lord Saga mengirim surat untuk Anda,"
ujar Minoru, mengeluarkan gulungan kertas.
"Beliau pasti menulisnya tadi malam. Beliau
sangat menghormati Anda."
"Biar kulihat." Tulisannya menggambar-
kan orangnya, tebal dan ditekan, guratan
tinta kelihatan hitam dan legas, bergaya
kotak.
"Beliau mengucapkan selamat padaku atas
keramahan Kaisar padaku, dan atas ke-
berhasilan hadiahku, serta mengucapkan
semoga berhasil hari ini."
"Beliau khawatir atas popularitas Anda,"
ujar Minoru. "Dan takut bila Anda kalah
dalam pertandingan itu, Kaisar masih tetap
mendukung Anda."
"Aku akan mematuhi kesepakatan, dan
aku berharap dia pun begitu," sahut Takeo.
"Beliau mengharapkan Anda menemukan
cara untuk berkelit dari kesepakatan tersebut,
agar beliau mendapat alasan untuk tidak
menepatinya."
"Minoru, sikapmu menjadi begitu sinis!
Lord Saga adalah bangsawan besar berasal
dari klan kuno. Dia telah mengumumkan
kesepakatannya. Dia takkan mengingkari
kesepakatan itu tanpa membuat dirinya tidak
terhormat, dan begitu pula aku!"
"Persis seperti itulah cara bangsawan men-
jadi besar," gumam Minoru.
***
Jalanan jauh lebih ramai lagi dibanding
kemarin, dan masyarakat menari-nari seperti
kesurupan. Cuaca makin panas dengan
kelembapan yang menandakan hujan plum.
Arena di Biara Agung dipenuhi penonton:
perempuan mengenakan kimono bertudung,
laki-laki berpakaian cerah, anak-anak, semua
memegang payung dan kipas. Di dalam
lingkaran terluar pasir merah para pe-
nunggang kuda menunggu: kuda tim Saga
memiliki sabuk kulit yang dikaitkan di
bawah ekor serta tali dada berwarna merah,
sedangkan milik Shigeko berwarna putih.
Pelana kuda dilapisi kerang mutiara; surai
dikepang; jambul dan ekornya mengkilat
serta sehalus rambut seorang putri. Seutas tali
jerami kuning membagi lingkaran sebelah
luar dari lingkaran yang sebelah dalam,
dengan pasir berwarna putih.
Takeo bisa mendengar gongongan anjing
yang bersemangat dari sisi timur arema,
tempat sekitar lima puluh ekor anjing dalam
sebuah kerangkeng berhiaskan daun dan
rumbai-rumbai putih. Di bagian belakang
lapangan terdapat bilik dari kain sutra
didirikan bagi Kaisar, yang tersembunyi
seperti sebelumnya, di balik tirai bambu.
Takeo dibimbing ke tempat di sebelah
kanan bilik Kaisar. Di tempat itu Takeo
disambut para bangsawan, ksatria dan istri
mereka, sebagian sudah bertemu dengannya
sehari sebelumnya. Pengaruh kirin sudah
tampak: seorang laki-laki memperlihatkan
padanya pena lintang yang diukir mengikuti
bentuk kirin, dan beberapa perempuan
mengenakan tudung berhiaskan gambar
kirin.
Suasana hari itu terasa bagai piknik di
pedesaan, meriah dan ramai, dan Takeo
berusaha ikut ambil bagian di datamnya
dengan sepenuh hati. Namun sesekali
pemandangan tampak kabur dan langit
semakin kelam, dan mata dan pikirannya
dipenuhi dengan bayangan-bayangan Taku
yang tertembak di leher lalu mati kehabisan
darah.
Ia mengalihkan perhatian pada mereka
yang masih hidup, pada perwakilannya,
Shigeko, Hiroshi dan Gemba. Kedua kuda
abu-abu pucat dengan surai dan ekor hitam
terlihat sangat kontras dengan kuda Gemba
yang berbulu hitam. Kuda-kuda melangkah
tenang mengelilingi lingkaran. Saga me-
nunggang kuda besar dengan bulu warna
coklat kemerahan. Kedua pendukungnya,
Okuda dan Kono, menunggang kuda belang
dan juga merah bata. Busur milik mereka
jauh lebih besar dibandingkan dengan busur
Shigekodan ketiganya memiliki anak
panah yang dibului dengan bulu bangau
warna putih dan abu-abu.
Takeo belum pernah menyaksikan per-
buruan anjing, dan peraturan permainan itu
dijelaskan oleh kawan pendampingnya.
"Anda hanya boleh menembak bagian ter-
tentu di tubuh anjing: punggung, kaki, leher.
Anda tidak boleh menembak kepala, bagian
lunak di perut atau kematuan, dan nilai Anda
akan dikurangi jika anjingnya berdarah atau
mati. Makin banyak darah menetes, makin
buruk tembakannya. Ini semua tentang
pengendalian sempurna yang sangat sulit
dicapai sewaktu kuda berderap."
Mereka berkuda dalam barisan menurut
urutan pangkat, dari yang terendah sampai
yang tertinggi, pasangan pertama Okuda dan
Hiroshi.
"Okuda akan mulai lebih dulu untuk
menunjukkan cara melakukannya," tutur
Saga kepada Hiroshi, dengan ramah, karena
penunggang kedua memiliki peluang lebih
menguntungkan.
Anjing pertama dibawa masuk ke
lingkaran: Okuda juga memasuki lingkaran
lalu menderapkan kudanya, membiarkan tali
kekang menggantung di leher kuda selagi dia
menaikkan busur panah dan menaruh anak
panahnya.
Tali anjing dilepaskan dan hewan itu
segera berjingkrakan, mengonggong pada
kuda yang tengah berderap. Anak panah
pertama Okuda berdesing melewati telinga
anjing itu, membuatnya menyalak kaget lalu
mundur, dengan ekor di sela kaki belakang-
nya. Anak panah kedua mengenai dada.
"Tembakan yang bagus!" seru laki-laki di
sebelah Takeo.
Tembakan yang ketiga terkena punggung
anjing yang tengah berlari. Anak panah itu
dilepaskan terlalu kuat: darah mulai menodai
bulu putih anjing itu.
"Kurang baik," adalah penilaian juri.
Takeo merasakan ketegangan mulai ber-
tambah saat Hiroshi memasuki lingkaran dan
Keri mulai berderap. Takeo sudah mengenai
kuda itu selama ia mengenai pemuda itu:
hampir delapan belas tahun. Mampukah
kuda abu-abu itu bertahan dalam per-
tandingan semacam ini? Akankah kuda itu
mengecewakan penunggangnya? Takeo tahu
Hiroshi mahir memanah, tapi mampukah
pemuda itu bersaing dengan pemanah nomor
satu dari ibukota?
Anjing dilepaskan. Mungkin anjing tiu
sudah melihat nasib kawannya dan tahu apa
yang menantinya dalam lingkaran itu; anjing
itu secepatnya berlari keluar lingkaran, meng-
hempaskan tubuhnya di antara anjing-anjing
lain. Anak panah Hiroshi luput mengenai
anjing itu sejauh serentangan kaki.
Anjing itu ditangkap, dibawa masuk lagi
dan dilepas sekali lagi. Takeo bisa melihat
kalau anjing itu ketakutan dan menggeram.
Anjing-anjing itu pasti mencium amis darah
sehingga ketakutan, pikirnya. Atau mungkin
anjing saling berkomunikasi lalu memper-
ingatkan. Kali ini Hiroshi lebih siap, tapi
anak panahnya tetap tidak kena sasaran.
"Lebih sulit dari kelihatannya,'' ujar
tetangga Takeo dengan simpatik. "Butuh
latihan selama bertahun-tahun."
Takeo menatap anjing itu saat dibawa
masuk untuk yang ketiga kalinya, berusaha
menyuruh agar anjing itu tenang. Ia tidak
mau Hiroshi menyakiti anjing itu, tapi ia
ingin pemuda itu setidaknya mendapat satu
nilai untuk bidikannya. Penonton terdiam:
di balik suara derap kuda, terdengar olehnya
senandung yang amat pelan, suara yang
dikeluarkan Gemba saat merasa gembira.
Tak ada orang lain yang bisa mendengar-
nya, tapi anjing itu bisa mendengarnya.
Hewan itu berhenti meronta dan menyalak.
Anjing itu tidak kabur saat dilepas, tapi
malah duduk dan menjilati bulunya sebelum
bangkit lalu berjalan pelan mengitari
lingkaran. Anak panah ketiga Hiroshi kena
bagian samping anjing itu, membuatnya ter-
jatuh dan menyalak, tapi tidak berdarah.
"Itu tembakan yang mudah! Okuda akan
memenangkan babak ini."
Juri memutuskan demikian. Tembakan
kedua Okuda, meski membuat si anjing ber-
darah, mendapat nilai lebih tinggi ketimbang
dua tembakan Hiroshi yang meleset,
Takeo bersiap menerima satu kekalahan
lagimaka tak peduli sebaik apa pun
Shigeko melakukannya, hasil pertandingan
sudah ditentukan. Matanya terpaku pada
Gemba yang tak lagi bersenandung, tapi
kelihatan sangat waspada. Kuda hitam
tunggangannya juga tampak was-pada,
menatap pemandangan asing dengan telinga
tegak dan bola mata mem besar. Lord Kono
menunggu di sebelah luar lingkaran di atas
kuda merah bata yang kuat sena penuh
semangat. Laki-laki itu mahir berkuda,
seperti yang sudah diketahui, dan kudanya
memang cepat.
Karena Hiroshi kalah pada babak sebelum-
nya, kali ini Gemba mendapat giliran per-
tama. Anjing yang berikutnya lebih lincah,
dan kelihatan tidak takut pada kuda yang
tengah berderap. Panah pertama Gemba
tampak melayang dan mendarat perlahan di
tungging anjing itu. Tembakan yang bagus,
dan tidak ada darah. Tembakannya yang
kedua hampir sama, sekali lagi tidak
mengeluarkan darah, tapi kini anjing itu
ketakutan, berlarian ke kanan dan kiri
melintasi lapangan. Tembakan ketiga Gemba
meleset. Kemudian Kono keluar dengan
menunggang kuda merah bata, membuat
kudanya berderap mengelilingi lingkaran
sebelah luar, membuat pasir merah
beterbangan. Para penonton berseru kagum.
"Lord Kono sangat mahir dan terkenal,"
orang di sebelah Takeo memberitahunya.
"Kemahirannya memang enak di-
pandang!" ujar Takeo setuju dengan sikap
sopan, seraya berpikir, aku akan kehilangan
segalanya, tapi aku takkan terlihat marah atau
sedih.
Anjing-anjing dalam kerangkeng makin
bersemangat; gonggongan berubah menjadi
lolongan, dan setiap anjing yang dibebaskan
semakin liar karena ketakutan. Namun tetap
saja Kono membukukan dua nilai tembakan
sempurna tanpa darah. Pada tembakan
ketiga, kuda tunggangannya terlalu ber-
semangat karena sorak sorai penonton, agak
meloncat saat Kono menarik busur.
Panahnya melayang di atas kepala anjing dan
kena bagian samping pangg:ung kayu di
belakangnya. Beberapa pemuda berlompatan
turun untuk mengambilnya, pemenang yang
beruntung mengayunkan anak panah itu di
atas kepalanya.
Setelah diskusi panjang para juri, babak
kedua diputuskan seri.
"Kini kita mungkin menunggu keputusan
Kaisar," seru laki-laki di sebelah Takeo.
"Cara ini sangat digemari pengunjung: bila
hasilnya seri secara keseluruhan."
"Tampaknya cara itu kurang sesuai karena
kurasa Lord Saga akan dianggap memiliki
lebih dalam olahraga ini."
"Tentu, Anda benar. Aku hanya tidak
ingin...." Laki-laki itu tak kuasa menahan
malu. Setelah diam dengan sikap canggung
selama beberapa saat, dia lalu mohon diri
menjauh untuk bergabung dengan kelompok
lain. Laki-laki itu berbisik kepada mereka,
dan Takeo mendengar kata-katanya dengan
jelas.
"Sungguh, aku tak tahan duduk di sebelah
Lord Otori saat dia menghadapi hukuman
mati. Aku nyaris tidak bisa menikmati
pertandingan karena mengasihani dirinya!"
"Kabarnya pertandingan ini hanyalah
alasan baginya untuk mengundurkan diri
tanpa kalah dalam perang. Lord Otori tidak
keberatan, maka kita tak perlu iba padanya."
Kemudian kesunyian melanda seluruh
arena sewaktu Shigeko memasuki lingkaran
dan Ashige mulai berderap. Takeo hampir
tidak sanggup memandang putrinya, namun
ia juga tak mampu memalingkan wajah.
Setelah peserta laki-laki, putrinya terlihat
kecil dan rapuh.
Meskipun penonton bersorak-sorai,
gonggongan anjing yang ketakutan, dan
ketegangan yang makin meningkat, baik si
kuda maupun penunggangnya tampak benar-
benar tenang. Gaya berjalan si kuda cepat
dan mulus. sedang si penunggang duduk
tegak dan tenang. Busur miniatur dan anak
panahnya membuat penonton terkesima, dan
berubah menjadi kekaguman saat anak
pertama menyentuh pelan bagian samping
tubuh anjing buruan. Anjing itu, terluka atau
ketakutan, mengibaskan anak panah itu
seakan hanya lalat. Kemudian anjing itu
seperti menganggap kalau ini adalah per-
mainan yang menyenangkan. Anjing itu
berlarian mengitari lingkaran di waktu yang
bersamaan dengan si kuda: Shigeko mem-
bungkuk dan melepaskan anak panah kedua
seolah benda itu adalah tangannya dan
tengah mengelus leher hewan itu. Si anjing
menggelengkan kepala dan mengibaskan
ekor.
Shigeko mendesak kudanya untuk ber-
derap lebih cepat dan anjing itu berlari
tunggang-langgang, moncong menganga,
telinga melambai-lambai. Mereka mengitari
arena sebanyak tiga kali seperti ini; kemudian
Shigeko menarik kudanya berhenti di depan
Kaisar. Anjing itu duduk di belakangnya,
berjingkrakan. Shigeko membungkuk dalam-
dalam, membuat kudanya berderap lagi, ber-
jalan memutar semakin mendekati anjing
yang duduk memerhatikan, memutar kepala-
nya, dengan lidah merah mudanya terjulur.
Anak panah ketiga terbang lebih cepat
namun tak kurang lembutnya, mengenai
anjing itu nyaris tanpa suara tepat di bawah
kepalanya.
Takeo tak kuasa mengagumi putrinya,
kekuatan dan kemahirannya yang diperkuat
dengan kelembutan. Dirasakan pelupuk
matanya menghangat, dan takut kalau rasa
bangga akan menghilangkan kesedihannya.
Takeo mengerutkan dahi lalu menahan agar
wajahnya tetap tanpa ekspresi, tidak meng-
gerakkan satu otot pun.
Saga Hideki, peserta terakhir, kini
menunggang kuda memasuki lingkaran
berpasir putih. Kuda coklat kemerahan itu
menarik-narik besi yang dipasang di mulutn-
ya, melawan penunggangnya, namun laki-
laki itu mengendalikan kuda dengan mudah.
Saga mengenakan jubah hitam, berhiaskan
bulu anak panah di bagian punggungnya,
dan kulit rusa di kedua paha untuk
melindungi kakinya, ekor pendeknya
menggantung hampir menyentuh tanah. Saat
dia mengangkat busur, penonton meng-
hembuskan napas; ketika dia menaruh anak
panah, mereka menahan napas. Kudanya
berderap, buih dari mulutnya beterbangan.
Anting dilepas: menggonggong dan me-
lolong, tubuh anjing itu terhempas ke tanah.
Anak panah Saga terbang lebih cepat dari
pandangan mata, mendapat nilai sempurna;
ke bagian samping tubuh si anjing dan
berhasil menjatuhkannya. Si anjing berusaha
bangkit terhuyung-huyung dan ke-
bingungan. Mudah bagi Saga untuk me-
nembaknya lagi dengan anak panah kedua,
sekali lagi ddak membuat anjing itu ber-
darah.
Matahari sudah di ufuk barat, hawa kian
panas, bayangan kian memanjang. Meskipun
orang-orang berteriak, anjing melolong, dan
anak-anak menjerit, namun Takeo tenang
sedingin es. Perasaan itu mematikan semua
perasaannya, menutupi semua kesedihan,
penyesalan dan amarah. Disaksikannya
dengan perasaan tanpa memihak selagi Saga
menderapkan kuda mengitari lingkaran lagi,
seorang laki-laki dengan pengendalian jiwa
dan raga yang sempurna. Pemandangan itu
tampak seperti dalam mimpi. Anak panah
terakhir melesat di samping badan si anjing
lagi dengan suara yang nyaris tak terdengar.
Pasti keluar darah, pikirnya, tapi bulu putih
si anjing atau pasir berwarna pucat itu tetap
bersih.
Semua orang terdiam. Takeo merasakan
semua mata tertuju pada dirinya, meskipun
ia tidak memandang siapa pun. Telah
dirasakannya kekalahan di tenggorokan,
perut, hingga empedunya. Saga dan Shigeko
setidaknya seri. Dua seri dan satu menang
Saga akan meraih kemenangan.
Tiba-tiba, di depan matanya, seolah masih
terus bermimpi, di pasir putih arena mulai
tercemar warna merah. Anjing tadi meng-
alami pendarahan hebat, dari mulut dan
anusnya. Penonton berseru kaget. Punggung
anjing itu melengkung, mencecerkan darah
berbentuk melengkung di pasir, men-
dengking satu kali, lalu mari.
Tenaga Saga terlalu besar, pikir Takeo. Dia
tidak bisa menundukkan kekuatan laki-
lakinya: dia bisa melambatkan anak panah,
namun tak mampu mengurangi tenaganya.
Dua tembakan pertama telah menghancur-
kan organ tubuh anjing itu dan mem-
bunuhnya.
Takeo seperti mendengar teriakan dan
sorak sorai yang berasal dari tempat jauh.
Perlahan ia bangkit, menatap ke ujung arena,
tempat Kaisar duduk di balik tirai bambu.
Pertandingan berakhir seri: kini keputusan
ada di tangan Kaisar. Perlahan-lahan pe-
nonton terdiam. Para peserta menunggu,
diam tak bergerak: kelompok merah di
bagian timur, sementara kelompok putih di
bagian barat. Bayang-bayang panjang kaki
kuda terbentang melintasi arena. Anjing-
anjing masih saja menyalak dari balik
kandang, tapi tidak ada suara lain.
Takeo menyadari kalau selama per-
tandingan orang-orang telah menjauhinya,
tak ingin menyaksikan terlalu dekat peng-
hinaan terhadap dirinya, atau berbagi takdir-
nya yang tidak menguntungkan. Kini ia
menunggu seorang diri untuk mendengarkan
hasilnya.
Terdengar bisikan dari balik tirai, tapi
Takeo sengaja menutup pendengarannya.
Hanya saat Menteri muncul dari balik tirai
dan dilihatnya pandangan resmi pertama ter-
tuju pada Shigeko, dan kemudian,
pandangan yang lebih gugup, tenuju pada
Saga, Takeo merasa ada secercah harapan.
"Karena kelompok Lady Maruyama tidak
menumpahkan darah, Kaisar menganugerah-
kan kemenangan kepada kelompok putih!"
Takeo berlutuT dan menyembah.
Kerumunan penonton bersorak menyetujui-
nya. Ketika Takeo duduk tegak, seketika
dilihatnya ruang di sekelilingnya telah
dipenuhi orang yang berhambur meng-
hampiri untuk memberinya selamat, ingin
dekaT dengannya. Ketika berita itu
menyebar ke seluruh penjuru arena dan di
luarnya, nyanyian pun mulai terdengar lagi.
Lord Otori telah muncul di ibukota;
Kuda-kudanya menggetarkan tanah kami.
Putrinya meraih kemenangan besar;
Lady Maruyama tidak menumpahkan darah.
Pasir tetap putih. Anjing pun tetap putih.
Para penunggang putih menang.
Tiga Negara hidup dalam damai;
Begitu pula Delapan Pulau
Takeo memandang ke arah Saga, dan
melihat bangsawan itu juga tengah
menatapnya. Tatapan mata mereka bertemu,
dan Saga menundukkan kepala sebagai peng-
akuan atas kemenangan itu.
Ini tidak seperti dugaannya, pikir Takeo,
lalu teringat kata-kata Minoru. Saga berharap
bisa menyingkirkan diriku tanpa berperang,
namun dia gagal. Dia akan memanfaatkan
alasan apa pun untuk mengingkari janjinya.
***
Lord Saga telah merencanakan mengadakan
jamuan makan besar untuk merayakan
kemenangannya yang sudah diketahui lebih
dulu; jamuan makan memang dilakukan
seperti yang direncanakan, namun berbeda
dengan kegembiraan tulus di jalan-jalan di
kota, perayaan tersebut tidak sepenuhnya
tulus. Kendati begitu, tata krama tetap ber-
laku, dan Saga mengumbar sanjungannya
kepada Lady Maruyama; semakin jelas kalau
dia menginginkan pernikahan itu lebih dari
sebelumnya.
"Kita akan menjadi sekutu, dan Anda akan
menjadi ayah mertuaku," ujar Saga, tertawa
dengan kegembiraan yang dipaksakan.
"Walaupun aku percaya usiaku lebih tua
beberapa tahun."
"Aku akan senang sekali memanggil Anda
putraku," sahut Takeo, dengan agak ter-
cengang selagi kata-kata itu meluncur dari
mulutnya. "Tapi kita harus menunda peng-
umuman pertunangan sampai putriku me-
minta pendapat klannya. Termasuk ibunya."
Takeo melihat sekilas ke arah Lord Kono dan
ingin tahu reaksi jujur bangsawan itu, di
balik sikap sopan yang ditunjukkannya;
pesan apa yang akan orang itu kirim pada
Zenko tentang hasil pertandingan ini, dan
apa yang tengah dilakukan Zenko?
Jamuan berlangsung hingga larut malam:
bulan sudah muncul dan bintang-bintang
tampak besar, cahayanya berpencar dan ber-
kabut dengan lembapnya udara.
"Aku minta kalian semua tidak pergi tidur
dulu," ujar Takeo ketika mereka kembali ke
kediaman. Ia membimbing Shigeko, Gemba
dan Hiroshi ke ruangan paling terpencil di
kediaman itu. Semua pintu terbuka lebar; air
bergemericik di taman dan sesekali nyamuk
berdengung. Minoru dipanggil.
"Ayah, ada apa?" tanya Shigeko segera.
"Apakah ada kabar buruk dari rumah
apakah Ibu? Adik bayiku?"
"Minora akan membacakannya," sahut
Takeo, dan memberi isyarat agar si jurutulis
mulai membaca.
Minora membaca tanpa perasaan, dengan
sikap dinginnya seperti biasa, tapi perasaan
mereka bertiga tidak kurang bergolaknya.
Shigeko menangis terang-terangan. Hiroshi
terduduk pucat pasi, seolah terkena pukulan
di dadanya lalu terhuyung-huyung. Gemba
berdengus keras lalu berkata, "Kau me-
rahasiakan ini seharian?"
"Aku tidak ingin konsentrasi kalian ter-
pecah. Aku tak menduga kalian akan
menang. Bagaimana aku harus berterima
kasih kepada kalian? Kalian tadi sangat luar
biasa!" Takeo bicara dengan berlinang air
mata penuh perasaan.
"Beruntung Kaisar cukup terkesan pada-
mu dan tak ingin menyinggung dewa-dewa
dengan memutuskan untuk menentangmu.
Segalanya bercampur aduk untuk meyakin-
kan dirinya bahwa kau memiliki restu dari
Surga."
"Kurasa dia memutuskan ini agar men-
dapatkan orang yang bisa mengimbangi
kekuatan Saga," sahut Takeo.
"Itu juga," Gemba setuju. "Tentu saja, dia
manusia setengah dewatapi juga tak ber-
beda dengan kita semua, termotivasi oleh
gabungan antara idealisme, pragmadsme,
penyelamatan diri sendiri dan niat yang
baik!"
"Kemenangan kalian membuat Kaisar ber-
pihak pada kita," ujar Takeo. "Tapi kematian
Taku berarti kita harus segera kembali.
Zenko harus dihadapi sekarang juga."
"Ya, kurasa kini waktunya kita pulang,"
sahut Gemba. "Bukan hanya karena Taku,
tapi demi mencegah kekacauan lebih jauh
lagi. Ada satu hal lagi yang tidak beres."
"Berkaitan dengan Maya?" tanya Shigeko
dengan ketakutan yang terdengar dalam nada
suaranya.
"Mungkin," sahut Gemba tanpa berkata
lagi.
"Hiroshi," ujar Takeo. "Kau telah
kehilangan sahabat terdekatmu... Aku
menyesal."
"Aku berusaha menahan keinginanku
untuk balas dendam." Suara Hiroshi
terdengar parau. "Yang kuinginkan hanyalah
kematian Zenko, begitu pula dengan Kikuta
Akio dan putranya. Naluriku mengatakan
kalau kita haras segera pergi dan memburu
merekatapi Ajaran Houou menahanku
untuk tidak melakukan kekerasan. Lalu
bagaimana cara kita menghadapi para pem-
bunuh ini?"
"Kita memang akan memburu mereka,"
sahut Takeo. "Tapi akan dilakukan dengan
adil. Aku telah diakui Kaisar, kekuasaanku
telah ditegaskan oleh Paduka Yang Mulia.
Zenko tidak memiliki lagi dasar hukum yang
sah untuk menentangku. Bila dia tidak
benar-benar tunduk, kita akan mengalah-
kannya dalam pertempuran dan dia akan
mencabut nyawanya sendiri. Akio akan
digantung seperti penjahat biasa. Tapi kita
harus pergi secepatnya."
"Ayah," ujar Shigeko. "Aku tahu Ayah
benar. Tapi tidakkah kepergian yang tergesa-
gesa akan menyinggung Lord Saga dan
Kaisar? Dan jujur saja, aku cemas pada
keadaan kirin. Kesehatannya merupakan
masalah terpenting bagi kelangsungan
kedudukan Ayah. Hewan itu akan ketakutan
bila kita semua pergi begitu mendadak. Tadi-
nya aku berharap bisa melihatnya tenang
dulu sebelum kita pergi.... Mungkin aku bisa
tinggal di sini menemaninya?"
"Tidak, Ayah takkan meninggalkan dirimu
di tangan Saga," sahutnya dengan suara keras
yang mengejutkan mereka sendiri. "Apakah
aku harus menyerahkan semua putriku
kepada musuh-musuhku? Kita telah berikan
kirin kepada Kaisar. Kaisar dan orang-
orangnya yang harus bertanggung jawab atas
nasib hewan itu. Kita harus pergi sebelum
akhir minggu: kita akan memanfaatkan
cahaya bulan antara bulan sabit dan bulan
purnama untuk melakukan perjalanan."
"Kita akan berkuda di tengah hujan, dan
mungkin tak melihat bulan sama sekali,"
gumam Hiroshi.
Takeo berpaling ke arah Gemba. "Gemba,
kau telah membuktikan kalau dirimu tahu
segalanya sejauh ini. Apakah Surga masih
terus berpihak pada kita dengan menunda
hujan plum?"
"Kita lihat saja apa yang bisa kita laku-
kan," sahut Gemba berjanji sambil senyum,
di sela-sela air matanya.*
Sejak Takeo memintanya mengambil alih
kepemimpinan Tribe, Muto Shizuka telah
melakukan perjalanan ke hampir seluruh
Tiga Negara. Dia mengunjungi desa-desa ter-
sembunyi di pegunungan dan rumah-rumah
pedagang tempat kerabatnya menjalankan
berbagai usaha: membuat sake, fermentasi
kedelai, peminjaman uang, hingga kegiatan
mata-mata. Hierarki kuno Tribe masih tetap
ditegakkan dengan struktur vertikalnya serta
kesetiaan tradisional keluarga, yang berarti
bahkan dalam kalangannya sendiri. Tribe
menyimpan rahasia dan sering bertindak
dengan cara mereka sendiri.
Seperti biasa Shizuka disambut dengan
sopan santun terta penghormatan, namun ia
sadar ada sakit hati terhadap posisi barunya:
andai Zenko mendukung, keadaannya pasti
berbeda; tapi sadar selagi putranya itu masih
hidup, maka ketidakpuasan di dalam
keluarga Muto bisa berkembang menjadi
sikap membangkang. Karena alasan itulah
dia merasa berkewajiban untuk memper-
tahankan kontak dengan semua kerabatnya,
berusaha agar mereka tetap setia kepadanya,
dan menentang putra sulungnya.
Shizuka tahu betul kalau ada rahasia yang
disimpan dan ketidakpatuhan berkembang di
kalangan Tribe; karena, bertahun-tahun lalu,
dia pernah mengungkapkan cara kerja
pekerjaan Tribe kepada Shigeru, dan catatan
terperinci itu yang memungkinkan Takeo
mengalahkan dan mengendalikan Tribe.
Kenji sudah tahu tindakannya itu, dan telah
memilih untuk mengabaikan satu hal yang
bisa disebut pengkhianatan; tapi Shizuka
sendiri selalu ingin tahu siapa lagi yang
mungkin mencurigai dirinya. Orang-orang di
kalangan Tribe memiliki ingatan yang
panjang, dan juga sabar dan pantang
menyerah ketika berkaitan dengan balas
dendam.
Tak lama setelah Takeo berangkat ke
Miyako, Shizuka bersiap pergi lagi, pertama
ke Yamagata lalu ke Kagemura di pe-
gunungan di belakang Yamagata, kemudian
ke Hofu.
"Kaede dan bayi laki-lakinya kelihatan
sangat sehat, aku merasa aku bisa pergi
sebelum hujan plum tiba," tutur Shizuka
pada suaminya. "Kau ada di sini untuk
merawat mereka, kau tak boleh bepergian
dengan Fumio tahun ini."
"Bayi ini sangat kuat," sahut Ishida setuju.
"Tapi kau takkan tahu apa akan terjadi pada
bayi: cengkeraman mereka pada kehidupan
masih lemah, dan bisa terlepas tanpa terduga.
Tapi bayi ini tampak seperti pejuang cilik."
"Dia adalah ksatria sejati," sahut Shizuka.
"Kaede amat memujanya!"
"Belum pemah aku melihat seorang ibu
begitu terpesona pada anaknya sendiri," aku
Ishida.
Kaede hampir tidak sanggup berpisah dari
anaknya. Dia merawatnya sendiri, yang tidak
dilakukannya pada anak-anaknya yang lain.
Shizuka melihat itu dengan rasa iri ber-
campur iba: konsentrasi penuh si bayi
mengisap puting susu ibunya, perlindungan
sang ibu yang sama kuatnya.
"Anak ini akan diberi nama siapa?" tanya-
nya.
"Kami belum memutuskan," jawab Kaede.
"Takeo sangat suka nama Shigeru, tapi nama
itu berkaitan dengan hal-hal yang menyedih-
kan, dan kami telah memiliki Shigeko.
Mungkin nama Otori yang lainnya, Takeshi,
Takeyoshi. Tapi anak ini takkan diberi nama
sampai berusia dua tahun nanti. Aku me-
manggilnya singa kecilku."
Shizuka teringat betapa ia amat sayang
kepada kedua putranya saat mereka masih
kecil, merenungkan kekecewaan dan ke-
cemasan yang mereka timbulkan saat ini.
Sewaktu menikah dengan Ishida, Shizuka
berharap bisa punya anak lagi, tapi tahun-
tahun berlalu dan ia tidak juga hamil. Kini ia
jarang mendapat haid; kesempatannya
hampir habis: dan tentu ia tak ingin harapan-
nya terkabul. Ishida tidak punya anak dari
pernikahan sebelumnya: istrinya sudah
meninggal bertahun-tahun lamanya; meski
tadinya dia ingin menikah lagi, tapi tak satu
pun calon yang diterima oleh Lord Fujiwara.
Ishida adalah laki-laki yang penuh cinta, serta
sangat baik hati. Shizuka pernah mengatakan
kepada Takeo, kalau ia cukup bahagia hidup
tenang bersama Ishida di Hagi dan bisa terus
mendampingi Kaede. Tapi sejak menyetujui
untuk menjadi ketua keluarga Muto dan
Tribe, tugas itu menyita tenaga dan waktu-
nya. Itu juga berarti ada banyak persoalan
yang tak bisa dibicarakannya dengan Ishida:
Shizuka mencintai suaminya, dan suaminya
itu memiliki banyak sifat baik yang
dikaguminya, tapi tutup mulut tidak ter-
masuk di dalamnya. Ishida tidak terlalu
memikirkan mana yang bisa dibicarakan
dengan orang banyak serta mana yang harus
dirahasiakan. Sake bahkan bisa lebih me-
longgarkan lidahnya, dan bisa saja lupa
dengan apa yang telah diocehkannya di
malam sebelumnya. Ishida menyukai semua
kesenangan dari kedamaianmakanan yang
berlimpah, kebebasannya untuk bepergian,
berinteraksi dengan orang asing, benda-
benda indah yang mereka bawa dari bagian
dunia lainhingga pada tahapan tidak ingin
menghadapi kenyataan bahwa kedamaian
selalu berada di bawah ancaman, bahwa tidak
semua orang bisa dipercaya, bahwa musuh
bisa saja berada dalam lingkungan keluarga-
nya sendiri.
Maka Shizuka tidak mengutarakan pada
suaminya tentang Taku dan Zenko, dan
Ishida pun sudah hampir melupakan malam
di Hofu ketika dalam keadaan mabuk di-
ungkapkannya kepada Zenko, Hana dan
Lord Kono tentang teori kekuatan pikiran
manusia, serta efek menyembuhkan diri
sendiri dengan percaya kepada ramalan, dan
bagaimana semua ini berlaku pada diri
Takeo.
Sunaomi dan Chikara sedih atas kepergian
Shizuka, tapi ibu mereka, Hana, diharapkan
berada di Hagi sebelum akhir bulan, dan
mereka berdua terlalu disibukkan dengan
pendidikan dan latihan untuk bisa merindu-
kan neneknya. Sejak mereka berdua tinggal
di Hagi, Shizuka mengamati keduanya
dengan cermat untuk melihat apakah ada
tanda kemampuan yang berkembang, tapi
kedua anak itu kelihatan layaknya putra
ksatria, tak berbeda dari anak lelaki seusia
mereka yang berlatih bersama mereka, saling
bersaing dan bertengkar.
Kaede memeluk, memberinya jubah baru
dengan tudung model baru dan seekor kuda
dari istal, kuda betina yang sudah sering
ditunggangi Shizuka. Ia merasa lebih mudah
mendapatkan kuda ketimbang teman seper-
jalanan: tersadar kalau ia merindukan Kondo
Kiichi yang bisa menjadi teman yang
sempurna untuk perjalanan semacam ini,
dengan keahlian bertarung dan kesetiaannya;
disesalinya kematian Kondo, dan ia pun
mendoakannya.
Ia menolak tawaran Kaede untuk dikawal
ksatria Otori, dan memilih Bunta sebagai
teman perjalanan. Bunta dulu menjadi
informannya yang bekerja sebagai pelayan di
kediaman Lady Maruyama Naomi, dan
menetap di Inuyama setelah kematian
majikannya itu. Setelah perang dan gempa,
laki-laki itu menemukan jalannya ke Hagi,
dan sejak saat itu bekerja melayani keluarga
Otori. Usianya beberapa tahun lebih muda
dari Shizuka, berasal dari keluarga Imai.
Penampilannya kalem dan pendiam, namun
sebenarnya dia pencopet ulung, pendongeng
dengan keterampilan mengorek informasi,
dan jago sumo dan petarung tangan kosong
yang tangguh. Masa lalu yang mereka lalui
bersama telah menciptakan ikatan antara
mereka berdua, dan Shizuka merasa bisa
memercayainya.
Sepanjang musim dingin Bunta telah
membawakannya potongan-potongan kecil
informasi, dan begitu salju mencair, dia pergi
ke Yamagata atas permintaan Shizuka untuk
mencari informasi. Kabar yang dibawanya
sungguh mengganggu: Taku belum kembali
ke Inuyama dan masih di Hofu; Zenko
terlibat hubungan erat dengan Kikuta dan
menganggap dirinya sebagai ketua Muto;
keluarga Muto berbeda pendapat. Masalah
ini telah ia bicarakan dengan Takeo, tapi
mereka belum memutuskan apa pun.
Kelahiran putranya, persiapan untuk per-
jalanan ke Miyako telah menyita perhatian
Takeo. Kini Shizuka merasa berkewajiban
untuk bertindak sendiri: berusaha memper-
tahankan agar keluarga Muto tetap setia dan
memastikan keamanan si kembar, Maya dan
Miki.
Shizuka menyayangi mereka berdua seperti
putri yang tidak pernah dimilikinya. Dia
yang merawat mereka ketika Kaede mem-
butuhkan waktu yang begitu lama untuk me-
mulihkan diri setelah melahirkan; dialah
yang mengawasi semua latihan mereka
dengan cara Tribe; dia pula yang telah
melindungi dan membela mereka dari semua
orang yang hendak menyakiti mereka.
Ia punya harapan lain yang ia tak yakin
mampu mewujudkannya, tujuan yang
pernah diajukan namun ditolak Takeo.
Shizuka tak kuasa menahan ingatannya pada
Iida Sadamu, dan rencana untuk membunuh
bangsawan itu. Andai dunia sejujur seperti
sekarang ini. Ia telah mengatakan pada
Takeo bahwa sebagai Ketua Muto dan
sahabat keluarga Otori, ia menganjurkannya
untuk menyingkirkan Zenko. Ia masih tetap
berpegang pada pendapatnya saat memikir-
kannya dengan pikiran yang jernih. Tapi
ketika memikirkannya sebagai seorang ibu...
Takeo sudah mengatakan kalau dia tak
ingin membunuh Zenko, pikirnya. Aku tidak
perlu melakukan hal yang bertentangan dengan
keinginannya. Tak seorang pun akan
menyangka usulan itu datang dariku.
Tapi di lubuk hatinya, Shizuka meng-
harapkan anaknya itu mati ditangannya
sendiri.
Putra Bunta, pemuda berusia lima belas
atau enam belas tahun, ikut bersama mereka
untuk mengurus kuda, menyediakan makan,
dan berkuda di depan untuk mengatur
tempat pemberhentian selanjutnya. Cuaca
hari itu cerah, jalanan aman dan terawat
baik, kota-kota damai dan sejahtera,
makanan berlimpah dan lezat.
Shizuka kagum atas semua yang Takeo
dan Kaede capai demi kemakmuran dan
kebahagiaan negara, dan meratapi hasrat
yang haus kekuasaan dan keinginan kuat
untuk balas dendam yang mengancamnya.
Tapi tidak semua orang tidak menikmati
kedamaian dan kemakmuran di negeri ini.
Keluarga Muto tempat dia menginap di
Tsuwano menggerutu karena berkurangnya
status mereka di kalangan pedagang sejak
banyak orang yang terlibat dalam per-
dagangan. Di Yamagata, di rumah lama
Kenji yang kini ditinggali sepupunya, Yoshio,
perbincangan selalu soal kemakmuran di
masa lalu, ketika Kikuta dan Muto ber-
sahabat dan semua orang takut dan meng-
hormati mereka.
Ia telah mengenal Yoshio sejak kecil
karena mereka pernah dilatih bersama. Dia
memperlakiikan Shizuka dengan akrab dan
berbicara blak-blakan. Shizuka tak tahu
apakah ia bisa mengandalkan dukungan
sepupunya ini, tapi setidaknya sepupunya ini
bersikap jujur.
"Ketika Kenji masih hidup," tutur Yoshio.
"Semua orang menghormatinya, dan bisa
melihat alasannya untuk berdamai dengan
Otori. Takeo memiliki informasi yang bisa
menghancurkan Tribe, seperti yang dilaku-
kannya sebelumnya di Maruyama. Lalu,
banyak hal yang harus ditakukan: memberi
kita waktu, dan menyimpan tenaga. Tapi
semakin banyak orang mengatakan kalau
tuntutan Kikuia akan keadilan perlu
didengar: Takeo bersalah atas penghinaan
yang terburuk, lari dari Tribe dan mem-
bunuh Ketua dari keluarganya. Selama ber-
tahun-tahun dia belum dihukum atas per-
buatannya, tapi kini Akio dan Arai Zenko
siap menghukumnya."
"Kenji bersumpah setia pada Takeo atas
nama keluarga Muto," Shizuka mengingat-
kan. "Begitu pula putrakudia telah ber-
sumpah berulang kali. Dan aku memimpin
keluarga Muto bukan hanya karena Takeo
menunjukku: ini juga keinginan Kenji."
"Kenji tak bisa bicara dari dalam
kuburnya, kan? Itulah keprihatinan kami
aku jujur padamu, Shizuka. Aku senantiasa
kagum dan juga suka padamu, walaupun
dulu kau anak yang menyebalkan, tapi kau
sudah berubah: bahkan sempat cukup cantik
juga!" Yoshio menyeringai dan menuangkan
sake lagi untuknya.
"Simpan saja pujianmu itu," balasnya,
sambil minum sake dengan sekali tenggak.
"Aku sudah terlalu tua untuk itu sekarang!"
"Kau minum dan bertarung layaknya laki-
laki!" seru Yoshio dengan kagum.
"Aku pun bisa memimpin layaknya laki-
laki," Shizuka meyakinkannya.
"Aku tak menyangsikannya. Tapi seperti
yang kukatakan, orang-orang di Tribe ter-
singgung karena Takeo yang menunjukmu.
Masalah dalam keluarga Muto tidak pernah
diputuskan oleh bangsawan"
"Takeo bukan sekadar bangsawan!" protes
Shizuka.
"Bagaimana dia mendapatkan kekuasaan?
Layaknya bangsawan lain, dengan meraih
kesempatan, menghadapi musuhnya dengan
kejam, dan mengkhianati mereka yang telah
bersumpah setia kepadanya."
"Itu hanya salah satu sisinya!"
"Itu adalah cara Tribe," sahut Yoshio,
tersenyum lebar.
Shizuka berkata, "Bukti keberhasilan
pemerintahannya ada di mana-mana: tanah
yang subur, anak-anak yang sehat, pedagang
yang kaya."
"Ksatria yang frustrasi dan mata-mata yang
menganggur," bantah Yoshio, menenggak
sakenya lalu mengisi lagi. "Bunta, kau diam
saja. Katakan kalau aku benar."
Bunta mengangkat mangkuk ke mulutnya
dan menatap Shizuka dari pinggiran
mangkuknya selagi minum. "Bukan hanya
karena Takeo yang menunjukmu, tapi juga
karena kau perempuan. Ada kecurigaan lain
pada dirimu yang jauh lebih berat."
Senyum Yoshio hilang, dia duduk dengan
bibir terkatup rapat dan menunduk.
"Orang-orang ingin tahu bagaimana
Takeo menemukan Tribe di Maruyama
padahal dia belum pernah ke sana. Menurut
kabar, Lord Shigeru memiliki catatan
informasi tentang Tribe; orang tahu kalau
Lord Shigeru dan Kenji berteman, tapi
Shigeru tahu jauh lebih banyak tentang Tribe
dari yang bisa dia tahu dari Kenji. Pasti ada
orang yang memberi informasi padanya."
Kedua orang itu meliriknya, namun ia
tidak bereaksi.
"Orang-orang yang mengatakan kaulah
yang memberi informasi itu, dan itulah
alasannya Takeo menunjukmu sebagai ketua
Muto, sebagai imbalan atas pengkhianatan-
mu selama bertahun-tahun."
Kata-kata itu menggantung di udara bak
sebuah pukulan.
"Maaf," imbuh Bunta cepat. "Aku bukan-
nya mengatakan kalau aku salah satu dari
mereka; aku hanya ingin memperingatkan-
mu. Tentu saja Akio akan memanfaatkan
desas-desus ini."
"Itu sudah lama sekali," sahut Shizuka
dengan nada ringan. "Selama Iida berkuasa,
dan selama perang, banyak yang bertindak
yang dapat dianggap sebagai pengkhianatan.
Ayah Zenko menyerang Takeo setelah ber-
sumpah bersekutu dengannya, namun siapa
yang bisa menyalahkannya? Semua orang
tahu cepat atau lambat Arai akan melawan
Otori untuk mengendalikan Tiga Negara.
Otori menang: Tribe juga merasakan
kemenangannya, seperti yang sudah kita
lakukan, dan kita akan terus begitu."
"Uhh," gerutu Yoshio. "Sekarang nampak-
nya Arai akan menentang Otori lagi. Tidak
ada yang berpikir kalau Takeo akan meng-
undurkan diri dengan sukarela, apa pun hasil
pertandingan di Miyako. Dia akan kembali
dan bertempur. Dia bisa saja mengalahkan
Zenko di Barat, dan kemungkinan, meski
sedikit peluangnya, mengalahkan Saga di
Timur. Dia tak bisa menang melawan
mereka berdua. Kita harus memihak pada
pemenangnya...."
"Lalu Kikuta akan balas dendam," ujar
Bunta. "Mereka sudah lama menanti. Akan
terlihat kalau tidak ada yang bisa lepas dari
Tribe."
Shizuka mendengar kata-kata ini seperti
gema. Ia pernah mengucapkan kata-kata
yang sama tentang masa depan Takeo pada
Kaede bertahun-tahun lalu di Terayama.
"Kau bisa menyelamatkan diri, Shizuka,
dan kemungkinan juga keluarga Muto. Yang
mesti kau lakukan hanyalah mengakui Zenko
sebagai ketua keluarga. Kami melepaskan diri
dari Takeo sebelum dia kalah; kami tak ingin
terpuruk bersamanya, dan rahasia apa pun
yang kau simpan di masa lalu akan tetap
tersimpan rapat-rapat."
"Taku takkan setuju," sahut Shizuka
menyuarakan pikirannya.
"Dia akan setuju bila kau yang suruh,
sebagai ketua dan sebagai ibunya. Dia tidak
punya pilihan. Taku bisa berpikir dengan
akal sehat. Dia akan memahami kalau ini
demi yang terbaik. Zenko akan membayar
upeti pada Saga, Tribe akan bersatu lagi, kita
akan dapatkan kembali kekuatan kita.
Karena Saga berniat menyatukan Delapan
Pulau di bawah kekuasaannya, kita akan
punya pekerjaan yang menarik dan
menguntungkan selama bertahun-tahun yang
akan datang."
Dan aku tak perlu membunuh putraku,
pikir Shizuka.
***
Shizuka berangkat ke desa Muto, Kagemura,
keesokan harinya. Malam sebelumnya bulan
purnama dan ia berkuda dengan murung,
kesal dengan perbincangan semalam. Ia takut
kalau keluarga Muto di situ juga akan men-
desaknya untuk mengambil jalan yang sama.
Bunta hanya bicara sedikit, dan Shizuka
merasa marah dan tidak nyaman dengan laki-
laki itu. Sudah berapa lama Bunta curiga?
Apakah sejak pertama kali orang itu melapor-
kan tentang hubungan Shigeru dengan
Maruyama Naomi? Selama bertahun-tahun
ia takut pengkhianatannya akan terungkap,
namun sejak mengakui perbuatannya pada
Kenji, dan dimaafkan, rasa takut itu ber-
kurang. Kini rasa takut itu muncul lagi,
membuatnya waspada yang tidak ia lakukan
selama bertahun-tahun, siap bertarung mem-
bela diri. Ditemukan dirinya mengira-ngira
tentang Bunta dan anaknya, berusaha
memikirkan cara untuk menghabisi mereka
kalau mereka berbalik menentangnya.
Shizuka masih berlatih setiap hari, tapi ia
sudah tak muda lagi; ia bisa mengalahkan
banyak laki-laki dengan pedang namun juga
sadar kalau ia tidak bisa menandingi
kekuatan fisik mereka.
Hari menjelang malam ketika mereka tiba
di penginapan. Pagi harinya ia meninggalkan
bocah itu dan kuda di belakang. Ia berjalan
kaki seperti yang pernah ia lakukan bersama
Kondo, melintasi pegunungan. Shizuka tak
tidur karena gelisah. Ia hampir tak bisa
menahan diri untuk menangis. Tiada henti ia
memikirkan Kondo: ia pernah bercinta
dengan orang itu di tempat ini; ia tidak
mencintai Kondo; ia mengasihani orang itu.
Kemudian Kondo muncul lagi saat ia
mengira hidupnya akan berakhir, hanya
untuk melihat orang terbakar hidup-hidup di
depan matanya. Sifat Kondo yang sulit
menunjukkan perasaan seperti mendapatkan
kemuliaan tragis. Alangkah menyedihkan
keadaan Kondo saat itu, serta alangkah
mengagumkannya! Mengapa ia begitu
terharu pada laki-laki itu kini? Nyaris seperti
arwah Kondo tengah menggapai dirinya
untuk mengatakan sesuatu, untuk memper-
ingatkannya.
Bahkan saat melihat desa Muto di lembah
tersembunyi tak mampu membuatnya
gembira seperti biasanya. Hari sudah sangat
sore ketika mereka sampai, matahari mulai
tenggelam di balik gugusan pegunungan
terjal, kabut mulai menyelimuti lembah lagi.
Saat itu hawa terasa dingin, membuatnya
senang dengan jubah bertudung yang
dipakainya. Gerbang desa tampak dibuka
dengan rasa enggan. Bahkan rumah-rumah
di dalamnya berkesan tertutup dan tidak
ramah, dinding kayu kelam terkena embun,
atap-atap diperberat dengan bebatuan.
Kakek dan neneknya sudah lama
meninggal: rumah lama kini dihuni keluarga-
keluarga yang sebaya dengan kedua putranya
dan anak-anak; Shizuka tidak mengenal betul
mereka, walaupun ia tahu nama, bakat dan
sebagian besar rincian dalam hidup mereka.
Kana dan Miyabi, kini sudah menjadi
nenek, masih mengurus rumah, dan
setidaknya mereka menyambut dirinya
dengan kegembiraan yang tulus. Shizuka
kurang yakin dengan ketulusan sambutan
dari orang lainnya, meskipun anak-anak
sangat gembira atas kedatangannya, terutama
Miki.
Belum sampai dua bulan sejak terakhir kali
bertemu Miki: ia terkejut dengan perubahan
gadis itu. Miki lebih tinggi dan agak kurus
sehingga tampak lentur dan ramping.
Tulang-tulang tajam di wajahnya kelihatan
lebih menonjol dan matanya yang cekung
berkilat.
Sewaktu mereka berkumpul di dapur
untuk menyiapkan makan malam, ia
bertanya pada Kana, "Apakah Miki pernah
sakit?" karena saat musim semi kerapkali
terjadi demam mendadak dan sakit perut.
"Kau mestinya tidak berada di sini ber-
sama kami!" bentak Kana. "Kau tamu ke-
hormatan: seharusnya kau duduk bersama
para laki-laki."
"Aku akan bergabung dengan mereka
nanti. Ceritakan tentang keadaan Miki."
Kana berpaling ke arah Miki yang tengah
duduk di samping perapian, mengaduk sop
di panci besi yang tergantung di atas api
dengan kaitan besi berbentuk ikan.
"Miki memang semakin kurus," sahut
Kana setuju. "Tapi dia tidak mengeluh,
bukan begitu, 'nak?"
"Dia tidak megeluh," imbuh Miyabi
tertawa. "Miki setangguh laki-laki. Kemarilah
Miki, biarkan Shizuka memegang lengan-
mu."
Miki datang dan berlutut di dekat Shizuka
tanpa bicara. Shizuka mencengkeram lengan
bagian atas gadis itu. Dirasakakannya lengan
itu sekeras baja, tidak ada daging, hanya otot
dan tulang.
"Apakah semuanya baik-baik saja?"
Miki mengangguk.
"Ayo berjalan-jalan bersamaku: kau bisa
ceritakan apa yang membuatmu sedih."
"Dia akan bicara padamu saat tidak ingin
bicara dengan orang lain," ujar Kana dengan
suara pelan.
"Shizuka," bisik Miyabi bahkan lebih
pelan lagi. "Waspadalah. Para pemuda...."
Miyabi melirik sekilas ke ruang utama rumah
tempat suara-suara laki-laki terdengar samar-
samar, meski Shizuka bisa mengenali suara
Bunta. "Ada yang merasa tidak suka," ujar
Miyabi tidak jelas, terang-terangan takut ada
yang menguping.
"Begitulah yang diberitahukan kepadaku.
Di Yamagata dan Tsuwano juga sama. Aku
akan melanjutkan perjalanan ke Hofu,
tempat aku akan bicarakan keadaan ini
dengan kedua putraku. Aku akan pergi satu
atau dua hari lagi."
Miki masih berlutut di dekatnya, dan
Shizuka mendengarnya menghela napas
pelan dan merasakan kalau gadis itu semakin
tegang. Dirangkulnya Miki, tercengang
dengan tajam dan rapuhnya tulang di balik
kulitnya, tak ubahnya sayap burung.
"Ayo, pakai sandalmu. Kita akan jalan-
jalan ke biara dan memberi salam kepada
dewa-dewa."
Kana memberi Miki sedikit kue mochi
sebagai sesaji bagi dewa-dewa. Shizuka mem-
buka tudung jubahnya; cuaca terasa dingin.
Bulan bersinar redup menyinari udara yang
berkabut, membuat bayang-bayang di se-
panjang jalan dan di balik pepohonan yang
mengelilingi biara. Walau-pun sudah dua
hari sejak purnama bulan keempat, udara
masih terasa dingin. Jauh di ketinggian
pegunungan terdengar nyanyian katak dan
jangkrik. Hanya seruan burung hantu yang
tersendat-sendat.
Biara diterangi dua lentera di kedua sisi
altarnya. Miki menaruh kue mochi di depan
patung Hachiman, dan mereka berdua me-
nepukkan tangan lalu membungkuk hormat
tiga kali. Shizuka pernah memanjatkan doa
di sini bertahun-tahun yang silam untuk
Takeo dan Kaede. Sekarang ia masih me-
manjatkan permintaan yang sama, dan men-
doakan arwah Kondo dan mengucapkan rasa
terima kasihnya kepada laki-laki itu.
"Apakah para dewa akan melindungi
Maya?" tanya Miki, seraya menatap pahatan
patung di depannya.
"Kau sudah memintanya?"
"Sudah, aku selalu meminta begitu. Juga
untuk Ayah. Tapi aku tidak mengerti bagai-
mana para dewa bisa mengabulkan doa
semua orang, saat semuanya menginginkan
hal yang berbeda. Aku mendoakan ke-
selamatan Ayah, tapi banyak orang lain yang
mendoakan kematiannya."
"Inikah yang telah membuatmu kurus,
mencemaskan ayahmu?"
"Aku berharap bisa bersamanya. Dan
Maya juga."
"Terakhir kali kita benemu kau sangat
gembira, dan baik-baik saja. Apa yang telah
terjadl?"
"Aku tidak dapat tidur nyenyak. Aku takut
dengan mimpi."
"Mimpi apa?" sela Shizuka saat gadis itu
membisu.
"Mimpi-mimpi saat aku bersama Maya.
Dia menjadi si kucing dan aku menjadi
bayangannya. Kucing mengambil segala yang
ada dalam diriku dan aku harus mengikuti-
nya. Ketika berusaha terus terjaga, aku men-
dengar para laki-laki bicara: mereka selalu
membicarakan hal yang sama, tentang
keluarga Muto, dan apakah Ketua bisa
dijabat oleh perempuan, dan Zenko juga
Kikuta. Dulu aku senang berada di sini. Aku
merasa aman dan semua orang menyukaiku.
Sekarang para laki-laki terdiam saat aku
lewat, dan anak-anak lain menghindariku.
Ada apa Shizuka?"
"Para laki-laki memang selalu menggerutu.
Nanti juga mereka bosan," sahut Shizuka.
"Lebih dari itu," ujar Miki dengan nada
mendesak. "Sesuatu yang buruk sedang ter-
jadi. Maya dalam bahaya. Kau tahu bagai-
mana kami berdua: aku bisa tahu apa yang
terjadi pada Maya, begitu juga sebaliknya.
Kami selalu begitu. Aku bisa merasakannya
berseru memanggilku, tapi aku tidak tahu di
mana Maya berada."
"Maya ada di Hofu bersama Taku dan
Sada," sahut Shizuka dengan percaya diri
untuk menyembunyikan kegelisahannya
sendiri. Ia tahu benar si kembar bisa
mengetahui pikiran masing-masing dari jauh.
"Maukah kau mengajakku ke sana?"
"Mungkin sebaiknya begitu."
Tentu saja, pikirnya, aku harus mengajak-
nya. Aku tak bisa meninggalkannya di sini
Orang-orang akan memanfaatkan dia me-
lawan Takto. Semakin cepat aku bicara
dengan Taku dan Zenko, akan semakin baik.
Kami harus menyelesaikan masalah kepemim-
pinan ini sebelum perasaan tidak senang ini
makin tak terkendali
"Kita akan berangkat lusa."
***
Shizuka menghabiskan keesokan harinya
untuk berkonsultasi dengan para pemuda
yang kini membentuk inti keluarga Muto.
Mereka memperlakukannya dengan normat
dan mendengarkannya dengan sopan. Silsilah
keluarga, sejarah dan bakatnya telah
mengendalikan rasa hormat dan rasa takut
mereka. Shizuka lega, terlepas dari usia dan
bentuk tubuhnya yang kecil, ia masih bisa
mengendalikan mereka. Diulangi lagi niatnya
untuk membicarakan masalah kepemim-
pinan dengan Zenko dan Taku, serta
menekankan bahwa ia takkan turun dari
jabatannya sebagai Ketua sebelum Takeo
kembali dari wilayah Timur. Ia mengatakan
bahwa ini keinginan Kenji dan ia meng-
harapkan kepatuhan total mereka sesuai
tradisi keluarga Muto.
Tak seorang pun keberatan saat ia
mengatakan Miki akan ikut bersamanya, tapi
dua hari kemudian di jalan menuju
Yamagata, Bunta berkata, "Orang di desa
kini tahu kau tidak memercayai mereka
karena kau membawa Miki."
"Saat ini aku tidak memercayai siapa pun."
Mereka berkuda berdampingan, Miki di
depan menunggang kuda anak lelaki Bunta.
Shizuka berencana meminjam satu kuda lagi
dari istal Lord Miyoshi di Yamagata. Itu akan
membuat mereka berdua lebih leluasa, lebih
aman.
Shizuka memalingkan wajah lalu menatap
langsung ke arah Bunta, menantang laki-laki
itu. "Apa aku salah? Haruskah aku percaya
padamu?"
"Jujur saja, semua ini hanya masalah apa
yang diputuskan Tribe. Aku takkan meng-
gorok lehermu selagi kau tidur, kalau itu
yang kau maksud. Aku sudah lama
mengenalmudan lagi, aku tak suka mem-
bunuh perempuan."
"Jadi beritahu aku lebih dulu sebelum kau
mengkhianati diriku," ujarnya.
Mata agak Bunta mengerut. "Akan ku-
katakan."
"Suruh Bunta dan putranya pulang," ujar
Miki kemudian, ketika mereka tiba di
Yamagata dan sedang berdua saja. Tidak
ingin tinggal di rumah Muto dengan Yoshio,
Shizuka lalu pergi ke kastil. Di sana mereka
disambut istri Kahei yang membujuk mereka
agar tinggal lebih lama. Saat bujukannya
tidak berhasil, dia lalu menawarkan pen-
damping dan juga kuda tambahan.
"Sulit untuk memutuskan," ujar Shizuka
kepada Miki. "Jika aku kirim mereka pulang,
maka aku tidak punya lagi kontak dengan
keluarga Muto selama di perjalanan, dan aku
justru semakin mendorong Bunta untuk
menjauhiku; jika kuterima tawaran Lady
Miyoshi berarti kita akan bepergian secara
terbukakau sebagai putri Lord Otori."
Miki mengerutkan wajah pertanda tidak
menyukai usulan itu. Shizuka tertawa.
"Keputusan ini tidak pernah sesederhana
yang kau kira."
"Mengapa kita tidak pergi berdua saja?"
"Dua orang perempuan bepergian tanpa
pelayan atau pendamping justru akan lebih
menarik perhatianbiasa-nya perhatian yang
tidak diinginkan!"
"Andai kita dilahirkan sebagai laki-laki!"
ujar Miki, dan meski berusaha bicara dengan
nada ringan. Shizuka menangkap nada
kesedihan di balik kata-katanya. Teringat
olehnya rasa sayang Kaede pada bayi laki-
lakinya, kasih sayang yang tak pernah
ditunjukkan pada putri kembarnya. Ia
melihat kesepian yang dialami si kembar:
tumbuh dewasa di antara dua dunia. Bila
keluarga Muto berbalik menentang ayah
mereka, maka mereka pun akan menolak
kehadiran si kembar. Mereka bahkan akan
berusaha untuk menghabisi si kembar dan
Takeo.
"Bunta dan putranya akan ikut dengan
kita ke Hofu. Setibanya di sana, Taku akan
mengurus kita; kau akan bersama Maya dan
kita semua akan aman!"
Miki mengangguk dan berusaha ter-
senyum.
Malam itu terjadi gempa kecil, membuat
bangunan berguncang dan menyebabkan
kebakaran di beberapa bagian kota. Udara
tetap terasa penuh debu dan asap saat mereka
pergi dengan dua kuda tambahan, satu
ditung-gangi oleh pengurus kuda dari
kediaman Miyoshi. Mereka bertemu Bunta
dan putranya sesuai rencana, di tepi parit
lebar kota, tepat di luar gerbang kastil.
"Kau dapat kabar dari Taku?" tanya
Shizuka pada Bunta, seraya memikirkan
Taku mungkin menghubungi keluarga
Muto.
"Yoshio tidak mendengar kabar apa-apa.
Hanya ada laporan bahwa dia masih di
Hofu." Bunta menyeringai dengan kesan
tidak senonoh sewaktu mengatakannya, lalu
berkedip kepada putranya yang tertawa.
Apakah semua orang tahu kalau putranya
tengah tergila-gila pada Sada? Shizuka ber-
tanya pada dirinya sendiri, merasakan kesal
pada putra bungsunya itu.
Namun di malam pertama perjalanan
mereka, setelah Shizuka dan Miki pergi tidur,
Bunta mengetuk pintu dan memanggil
namanya pelan. Shizuka mencium bau sake.
"Keluarlah. Aku mendengar kabar buruk."
Bunta mabuk, sake sudah menghilangkan
kepekaan serta membebaskan lidahnya.
Shizuka mengambil pisaunya dari bawah
tikar dan menyelipkannya di balik jubah
tidurnya, sambil merapatkan jubah luarnya.
Diikutinya Bunta sampai ke ujung be-randa.
Bulan tidak kelihatan; terlalu gelap untuk
melihat ekspresi di wajah Bunta.
"Mungkin ini hanya rumor, tapi kurasa
kau perlu dengar." Dia berhenti sejenak lalu
bicara dengan canggung, "Ini bukan berita
bagus: kau sebaiknya menyiapkan diri."
"Apa?" tanya Shizuka, lebih keras dari
yang diingin-kannya.
"Taku diserang bandit. Dia dan kekasih-
nya, Sada, tewas."
"Tidak mungkin," ujar Shizuka.
"Tidak ada yang tahu detailnya. Tapi
orang-orang membicarakannya di kedai."
"Orang-orang Tribe? Muto?"
"Muto dan Kuroda." jawabnya canggung.
"Aku turut berduka."
Dia tahu kalau berita itu benar, pikirnya,
karena ia pun tahu kalau itu benar. Saat
merasakan kesedihan yang mendalam selama
perjalanan ke Kagemura, ia merasa arwah
Kondo berseru memanggil. Kini Taku berada
di antara mereka. Ini bisa membunuhku,
pikirnya. Penderitaan yang dirasakannya
begitu menusuk hingga tak tahu bagaimana
bisa bertahan, bagaimana ia bisa terus hidup
di dunia yang tak ada Taku di dalamnya.
Shizuka meraba pisau di jubahnya, ber-
maksud menikam lehernya sendiri, menyam-
but rasa sakit di tubuhnya yang bisa
mengakhiri penderitaannya. Tapi sesuatu
mencegahnya.
Shizuka memelankan suara, ingat kalau
Miki sedang tidur di dekat situ. "Putri Lord
Otori, Maya, ada bersama Taku. Apakah dia
juga ikut tewas?"
"Tidak ada yang menyebut-nyebutnya,"
sahut Bunta. "Kurasa tidak ada yang tahu
kalau Maya ikut bersama mereka, kecuali
keluarga Muto di Maruyama."
"Apakah kau tahu?"
"Aku dengar ada anak yang dijuluki Si
Kucing Kecil bersama Taku. Aku sedang
mencari tahu siapa orangnya."
Shizuka tidak menjawab. Ia tengah
berjuang mengendalikan diri. Di benaknya
melintas kenangan masa lalu, bayangan
pamannya, Kenji, saat mendengar kabar
tentang kematian putrinya di tangan Kikuta.
Paman, dipanggilnya arwah Kenji. Kau
mengerti penderitaan yang kualami saat ini
dan kini aku bisa rasakan sakit hatimu. Beri
aku kekuatan untuk terus hidup, seperti
dirimu.
Maya, aku harus memikirkan Maya. Aku
takkan memikirkan Taku, belum saatnya. Aku
harus selamatkan Maya.
"Apakah kita akan tetap ke Hofu?" tanya
Bunta.
"Ya, aku harus mencari tahu kebenaran-
nya." Ia memikirkan semua ritual yang harus
dilakukan bagi arwah Taku, ingin tahu di
mana putranya dikubur. Ia merasakan lilitan
penderitaan sekuat baja menghimpit dadanya
saat memikirkan jasad putranya di dalam
tanah, dalam kegelapan. "Zenko ada di
Hofu?" tanyanya, merasa kagum ternyata
kata-kata itu terlontar dengan tenang.
"Ya, istrinya pergi ke Hagi naik kapal laut
minggu lalu, tapi dia tidak ikut. Dia tengah
mengawasi pengaturan perdagangan dengan
orang-orang asing. Dia makin dekat dengan
mereka, begitulah beritanya."
"Zenko pasti tahu. Bila memang per-
buatan bandit, maka dia bertanggung jawab
untuk menangkap dan menghukum mereka,
dan menyelamatkan Maya bila masih hidup."
Namun bahkan saat ia bicara pun, Shizuka
tahu kalau putranya tidak tewas dibunuh
sembarangan bandit. Dan tak satu pun orang
Tribe berani menyentuh Takukecuali
Kikuta. Akio telah menghabiskan musim
dingin di Kumamoto. Akio pasti telah
berhubungan dengan Zenko.
Shizuka tak percaya Zenko terlibat dalam
kematian Taku. Apakah ia akan segera ke-
hilangan kedua putranya?
Aku tidak boleh menuduh sebelum bicara
dengannya.
Bunta menyentuh lengan Shizuka dengan
ragu-ragu. "Ada yang bisa kubantu? Mau
kuambilkan sake, atau teh?"
Ia menarik lengan, membaca sesuatu yang
lebih dari sekadar simpati dari gerakan
Bunta. Seketika membenci semua laki-laki
dengan nafsu dan kekerasan mereka yang
berujung pada kematian. "Aku ingin sendiri.
Kita pergi saat matahari terbenam. Jangan
katakan apa pun pada Miki. Akan kuputus-
kan kapan akan memberitahunya."
"Aku sangat berduka," sahut Bunta.
"Semua orang menyukai Taku. Ini benar-
benar kehilangan yang menyedihkan."
Ketika langkah kaki Bunta semakin meng-
hilang, Shizuka terpuruk di beranda. Ia
masih memegang pisau, alat yang bisa ia
gunakan untuk lari dari dunia nan penuh
derita ini.
Terdengar olehnya langkah kaki ringan di
lantai papan. Miki mendekat lalu memeluk-
nya erat.
"Kukira kau sudah tidur," Shizuka
memeluk gadis itu dan membelai rambutnya.
"Ketukan pintu tadi membuatku ter-
bangun, lalu aku tak tahan untuk men-
dengarkan." Tubuh kurusnya gemetaran.
"Maya belum mati. Aku pasti tahu kalau dia
sudah mati."
"Di mana dia? Bisakah kau menemukan-
nya?" Shizuka berpikir bila ia berkonsentrasi
pada Maya, pada mereka yang masih hidup,
maka ia takkan larut dalam kesedihan. Dan
Miki, dengan kepekaan yang amat tinggi,
nampaknya menyadari ini. Miki tidak meng-
ucapkan sepatah kata pun tentang Taku, tapi
membantu Shizuka berdiri.
"Kemari dan berbaringlah," katanya,
seolah Shizuka adalah anaknya. "Meskipun
tidak bisa tidur, kau bisa beristirahat. Aku
ingin tidur karena Maya berbicara padaku
dalam mimpi. Cepat atau lambat dia akan
mengatakan padaku di mana dia berada, dan
kemudian aku akan bertemu dengannya."
"Kita harus kembali ke Hagi. Aku harus
membawamu pulang."
"Tidak, kita harus ke Hofu," bisik Miki.
"Maya masih di Hofu. Bila kelak kau tidak
menemukanku, jangan cemas. Aku akan
bersama Maya."
Mereka berbaring dan Miki meringkuk di
sebelah Shizuka. Gadis itu sepertinya ter-
tidur, namun Shizuka tetap terjaga memikir-
kan tentang hidup putranya. Semua
perempuan di kalangan Tribe dan ksatria
harus membiasakan diri mendengar kabar
tentang kematian kejam putra mereka. Anak
laki-laki diajarkan untuk tidak takut mati,
dan anak perempuan dilatih untuk tidak
menunjukkan kelemahan atau kesedihan. Ia
melihat bagaimana kasih sayang seorang ibu
yang terlalu melindungi telah mengu-bah
putranya menjadi pengecut atau mengarah-
kan mereka bertindak gegabah. Taku telah
tiada, ia menangisinya, namun yakin kalau
kematian putranya karena tidak ingin
mengkhianati Takeo: Taku dibunuh karena
kesetiaannya. Kematiannya bukanlah sesuatu
yang tidak disengaja atau tidak bermakna.
Dengan cara ini Shizuka sanggup
menenangkan serta menguatkan dirinya
selama beberapa hari berikutnya saat berkuda
ke Hofu. Ia bertekad tidak akan bersikap
seperti seorang ibu yang kebingungan dan
bersedih, tapi bersikap sebagai ketua Muto; ia
takkan memperlihatkan kelemahan tapi
justru akan mencari tahu bagaimana putra-
nya bisa mati dan menyerei pembunuhnya
untuk dihukum.
***
Cuaca panas dan pengap: bahkan angin laut
tidak mampu mendinginkan kota pelabuhan
itu. Hujan musim semi hanya turun sedikit,
dan orang-orang bicara dengan cemas
tentang panasnya cuaca yang tidak biasa.
Cuaca seperti ini dapat menyebabkan
kekeringan karena selama enam belas tahun
atau lebih tidak terjadi kekeringan. Hujan
musim semi dan hujan plum senantiasa
datang di saat yang tepat sehingga banyak
pemuda yang belum pernah mengalami
kekeringan.
Suasana di kota terasa menggelisahkan,
bukan hanya karena cuaca. Berbagai pertanda
yang mengancam dilaporkan setiap hari;
wajah-wajah yang bicara tentang takdir
buruk terlihat di lentera-lentera di luar biara
Daifukuji; kawanan burung yang terbang
membentuk huruf nasib buruk di udara.
Segera setelah mereka tiba di sana, Shizuka
menyadari kesedihan dan kemarahan yang
sebenar-nya dari penduduk kota atas
kematian Taku. Ia tidak pergi ke kediaman
Zenko, tapi menginap di penginapan yang
menghadap ke sungai, tidak jauh dari
Umedaya.
Di malam pertama, pemilik penginapan
menceritakan kalau Taku dan Sada di-
makamkan di Daifukuji. Dikirimnya Bunta
untuk memberitahu Zenko tentang ke-
datangannya. Ia bangun pagi-pagi, me-
ninggalkan Miki yang masih tidur, berjalan
ke biara warna merah tua yang berdiri di
antara pepohonan suci, menghadap ke laut
untuk menyambut kepulangan para pelaut ke
Negara Tengah. Lantunan doa terdengar dari
dalam biara, dan dikenalinya kata-kata suci
dan alunan sutra bagi orang meninggal.
Dua biarawan tengah menyebarkan air di
papan jalan sebelum menyapunya. Salah satu
dari mereka mengenali Shizuka, lalu berkata,
"Ajak Lady Muto ke pemakaman. Aku akan
memberitahu Kepala Biara."
Dilihatnya simpati mereka, dan ia
berterima kasih.
Di bawah pepohonan besar terasa dingin.
Sang Biarawan membimbingnya ke makam
yang baru digali; belum ada batu nisan;
lentera menyala di sisi makam dan sese-orang
telah menaruh sesaji bungairis ungudi
depannya. Dipaksa dirinya membayangkan
putranya diletakkan dalam peti mati di
bawah tanah, tubuh yang kuat dan lincah
kini terbujur kaku. Arwah putranya pasti
gentayangan gelisah di antara dua dunia,
menuntut keadilan.
Biarawan yang kedua datang membawa
dupa, dan tak lama kemudian, saat Shizuka
berlutut berdoa tanpa suara, Kepala Biara
datang lalu berlutut di sampingnya. Mereka
tetap membisu beberapa saat; kemudian
Kepala Biara melantunkan suara yang sama
bagi orang meninggal.
Air mata mengambang di pelupuk mata-
nya dan mengalir turun di pipi. Kata-kata
kuno naik terbang ke bawah naungan pe-
pohonan, bercampur dengan kicau pagi
burung gereja serta kicau lembut burung
merpati.
Kemudian, Kepala Biara mengajaknya
masuk ke ruangannya dan menyajikan teh
untuknya. "Aku sendiri yang mengurus
pengukiran batu nisannya. Kurasa itulah
yang diinginkan Lord Otori."
Shizuka menatap orang itu. Ia mengenal
Kepala Biara selama beberapa tahun, tapi dia
selalu dalam suasana hati yang gembira, dia
bisa berkelakar dengan para pelaut dalam
dialek kasar mereka sama baiknya dengan
menggubah syair indah penuh humor ber-
sama Takeo, dan Tabib Ishida. Kini wajah-
nya murung, dengan ekspresi sedih.
"Apakah kakaknya, Lord Zenko, ber-
hubungan dengan semua ini?" tanya Shizuka.
"Aku khawatir Lord Zenko telah di-
pengaruhi orang asing: tidak ada peng-
umuman resmi, tapi semua orang mem-
bicarakannya. Dia telah menerima agama
mereka dan kini mengakuinya sebagai satu
agama yang benar. Hal ini membuatnya
tidak boleh masuk ke kuil dan biara kami,
dan tidak boleh melakukan upacara yang di-
perlukan bagi adiknya."
Shizuka menatap pendeta itu, tidak
percaya dengan apa yang didengarnya.
"Sikapnya sangat meresahkan," lanjutnya.
"Sudah ada pertanda kalau para dewa ter-
singgung. Orang-orang takut mereka akan
dihukum dewa atas perbuatan pemimpin
mereka. Sebaliknya, orang-orang asing itu
bersikeras kalau tuhan mereka, Deus, akan
memberi pahala bagi Zenko dan siapa pun
yang bergabung dengannya."
"Termasuk sebagian besar pengawal
pribadinya," imbuhnya, "yang diperintahkan
pindah agama atau mati."
"Benar-benar gila," ujar Shizuka, me-
mutuskan untuk bicara dengan Zenko
secepatnya. Ia tidak menunggu untuk di-
panggil menghadap, namun segera kembali
ke penginapan untuk berpakaian rapi dan
memesan tandu.
"Tunggu di sini," katanya pada Miki. "Bila
aku tidak kembali nanti malam, pergilah ke
Daifukuji, mereka akan mengurusmu."
Gadis itu memeluknya sangat erat.
Zenko keluar menuju beranda begitu
tandu diturunkan di dalam gerbang. Ia
memaksa dirinya berpikir kalau ia salah
menilai putra sutungnya itu. Kata-kata
pertama Zenko adalah simpati, diikuii
ungkapan betapa gembira dia bertemu
ibunya, terkejut karena ibunya tidak
langsung menemui dirinya.
Pandangan mata Shizuka jatuh ke kalung
rosario di leher Zenko, lambang agama orang
asing, menggantung di dadanya.
"Kabar buruk ini merupakan pukulan bagi
kita semua," ujarnya, selagi membimbing
ibunya berjalan menuju ruangan yang meng-
hadap ke taman.
Seorang bocah, cucunya, tengah bermain
di beranda, diawasi pengasuhnya.
"Kemari dan sapa nenekmu," panggil
Zenko, dan anak itu dengan patuh datang
lalu berlutut di hadapan Shizuka. Itu
pertama kalinya Shizuka bertemu cucunya:
usianya kira-kira dua tahun.
"Istriku, seperti yang Ibu tahu, sudah ke
Hagi untuk menemani kakaknya. Sebenarnya
dia enggan meninggalkan Hinomasa kecil,
tapi kukira sebaiknya mempertahankan se-
tidaknya salah satu putraku bersamaku."
"Jadi kau mengakui kalau kau memper-
taruhkan nyawa kedua putramu yang lain?"
tanya Shizuka pelan.
"Ibu, Hana akan bersama mereka dalam
dua minggu lagi. Kukira mereka tidak dalam
bahaya. Lagipula, aku tidak melakukan
kesalahan apa-apa. Tanganku bersih." Di-
angkat kedua tangannya lalu mengangkat
tangan putranya. "Lebih bersih dari tangan
Hinomasa," selorohnya.
"Dia punya telapak tangan Kikuta!" seru
Shizuka terkejut. "Mengapa kau tidak men-
ceritakannya?"
"Menarik, bukan? Darah Tribe tidak habis
terkikis." Zenko tersenyum lebar, dan mem-
beri isyarat pada pelayan perempuan itu
untuk membawa putranya pergi.
"Dia mengingatkanku pada Taku," tutur-
nya, sambil menyeka mata dengan lengan
baju. "Satu hal yang menghibur bila ternyata
adikku yang malang hidup dalam diri
putraku."
"Mungkin kau bisa ceritakan siapa yang
membunuhnya," ujar Shizuka.
"Bandit, tentu saja. Ada penjelasan apa
lagi? Aku akan kejar dan adili mereka. Tentu
saja, dengan Takeo sedang di Ibukota, orang-
orang yang putus asa semakin berani dan
keluar dari persembunyiannya."
Jelas sekali kalau Zenko tidak peduli bila ia
percaya atau tidak.
"Bagaimana kalau kuperintahkan kau
untuk memberitahu yang sebenarnya?"
Pandangan Zenko menghindar, dan
menyembunyikan wajahnya dengan lengan
baju lagi. Shizuka merasa kalau putranya itu
tidaklah menangis, tapi justru tersenyum,
senang dengan keberaniannya sendiri.
"Janganlah bicara tentang perintah me-
merintah, Ibu. Aku akan mematuhi semua
kewajibanku sebagai anak, tapi dalam hal
lain, sudah selayaknya Ibu mematuhiku,
sebagai Muto maupun sebagai Arai."
"Aku melayani Otori," sahutnya. "Begitu
pula Kenji, dan kau pun telah bersumpah
setia padanya."
"Ya, Ibu melayani Otori," ujarnya,
kemarahannya mulai terlihat. "Itulah yang
menjadi masalah selama bertahun-tahun.
Kemana pun kita melihat sejarah kebang-
kitan Otori, kita melihat tangan Ibudalam
penganiayaan Takeo atas Tribe, dalam pem-
bunuhan ayahku, bahkan dalam kematian
Lord Fujiwarakenapa Ibu tega meng-
khianati rahasia-rahasia Tribe kepada
Shigeru?"
"Akan kukatakan kepadamu! Aku meng-
inginkan dunia yang lebih baik bagi kau dan
Taku. Kurasa sudah semestinya kalian hidup
di dalam dunia Shigeru, bukan dunia yang
berisi pembunuh bayaran yang ada di
sekelilingku. Takeo dan Kaede menciptakan
dunia itu. Kami takkan membiarkan kau
menghancurkannya."
"Takeo sudah tamat. Apakah Ibu mengira
Kaisar akan berpihak padanya? Kalau pun dia
kembali, kami akan membunuhnya, dan aku
akan dinobatkan menjadi penguasa Tiga
Negara. Itu hakku dan aku sudah siap."
"Kau sudah siap melawan Takeo, dan
Kahei, Sugita, Sonodasebagian besar
ksatria Tiga Negara?"
"Takkan ada perang, yang ada hanyalah
kerusuhan. Dengan Saga di wilayah Timur,
sena dukungan tambahan yang kami miliki
dari orang-orang asing" Ditepuknya salib
di dadanya "Dengan senjata serta kapal
mereka, Takeo dapat dikalahkan dengan
mudah. Sebenarnya dia juga bukan benar-
benar ksatria: semua pertempurannya yang
terkenal itu hanya dimenangkan oleh
keberuntungan ketimbang keahlian."
Zenko memelankan suaranya. "Aku dapat
melindungi Ibu sampai tahap tertentu, tapi
bila Ibu bersikeras menentangku, aku tak
bisa menahan keluarga Kikuta. Mereka
menuntut Ibu dihukum, atas ketidakpatuhan
selama bertahun-tahun terhadap Tribe."
"Aku akan bunuh diri terlebih dulu," seru
Shizuka.
"Mungkin itulah keputusan terbaik,"
sahutnya, seraya menatap ibunya lekat-lekat.
"Bagaimana kalau kuperintahkan Ibu
melakukannya sekarang juga?"
"Aku mengandungmu dalam perut selama
sembilan bulan." Seketika Shizuka terkenang
saat ia menemui Kenji untuk mendapatkan
ijin dari Tribe agar bisa melahirkan anak ini.
Putranya adalah hadiah bagi kekasihnya:
betapa bangganya Arai saat itu. Kini ayah
dan anak telah memerintahkan kematiannya.
Kemarahan serta kesedihan menyelimuti
dirinya: menangis selama setahun takkan
mampu menguranginya. Bisa dirasakannya
akal sehatnya bergulir ke tepi kegilaan. Aku
berharap bisa mencabut nyawaku sendiri,
pikirnya, tergiur dengan pemusnahan yang
disebabkan oleh kematian; hanya nasib si
kembar yang mencegahnya. Ia ingin
menanyakan keberadaan Maya, tapi takut
mengungkap sesuatu yang mungkin Zenko
belum tahu. Lebih baik tutup mulut,
melakukan apa yang telah ia lakukan seumur
hidupnya, bersandiwara sebaik mungkin.
Shizuka berjuang membuang perasaannya
dan berpura-pura bersikap lembut.
"Zenko, kau putra sulungku, dan aku
ingin menjadi ibu yang baik dan berbakti
padamu. Aku akan memikirkan semua yang
kau katakan. Beri aku waktu satu atau dua
hari. Biarkan aku mengatur pemakaman
adikmu. Aku tak bisa memutuskan saat
diliputi kesedihan."
Selama beberapa saat Shizuka mengira
kalau putranya akan menolak keinginannya:
ia memperkirakan jarak antara taman dan
luar dinding, tapi dalam kesunyian ia seperti
mendengar desah napas sesorangadakah
penjaga yang bersembunyi di balik layar kasa,
di taman? Apakah dia takut aku akan
membunuhnya? Peluangnya lolos kecil. Ia
bisa menggunakan kemampuan menghilang:
jika para penjaga datang setelah ia mengalah-
kan seorang penjaga, mengambil pedang
penjaga itu....
Ternyata sisa-sisa rasa hormat masih
berhasil membujuknya. "Baiklah," akhirnya
Zenko berkata. "Aku akan meminta penjaga
mengawal Ibu. Jangan coba-coba kabur, dan
jangan sekali-sekali meninggalkan Hofu.
Ketika masa berkabung selesai, Ibu harus ber-
gabung denganku atau mencabut nyawa Ibu
sendiri."
"Kau akan datang untuk memanjatkan
doa bagi adikmu?"
Zenko melayangkan tatapan dingin,
diikuti gelengan yang tidak sabar. Shizuka
tak ingin memaksa karena takut Zenko akan
menahannya di sini, mungkin dengan
kekerasan. Shizuka membungkuk hormat,
merasakan kemarahan yang membara dalam
dirinya. Saat pergi, ia mendengar suara-suara
di ujung beranda utama. Ketika menoleh, ia
melihat Don Joao bersama jurubahasanya,
Madaren menghampiri. Mereka mengenakan
pakaian mewah, dan mereka berjalan dengan
rasa percaya diri yang baru.
Setelah memberi salam pada Don Joao
dengan sikap dingin, Shizuka lalu bicara pada
Madaren, tanpa sopan santun, "Kau pikir apa
yang sedang kau lakukan di sini?"
Madaren tersipu atas nada bicara Shizuka,
tapi berhasil mengumpulkan keberanian lalu
menjawab, "Melakukan kehendak Tuhan,
layaknya yang kita semua lakukan."
Tanpa menjawab Shizuka melangkah
masuk ke dalam tandu. Selagi tandu itu
digotong pergi dalam pengawalan enam
orang, dirutukinya orang-orang asing itu
karena mengganggu dengan kedatangan
senjata dan Tuhan mereka. Ia hampir tidak
ingat lagi kata-kata yang terlontar dari
mulutnya tadi: kemarahan dan kesedihan
membuat ia kacau; bisa dirasakannya
perasaan-perasaan itu menarik-narik dirinya
menuju kegilaan.
Sewaktu tandu diturunkan di luar
penginapan, Shizuka tidak segera turun. Ia
berharap bisa tetap berada dalam ruang
sempit yang mirip peti mati ini, dan tidak
berhubungan dengan orang yang hidup lagi.
Tapi ketika memikirkan nasib Miki, tatapan
matanya penuh amarah.
Bunta berjongkok di beranda, sama seperti
saat dia ditinggal, tapi kamar itu kosong.
"Di mana Miki?" tanyanya.
"Di dalam," sahut Bunta, terkejut. "Tidak
ada orang yang melewatiku, keluar atau
masuk."
"Siapa yang membawanya?" jantung
Shizuka mulai berdebar kencang ketakutan.
"Tidak ada, aku bersumpah."
"Sebaiknya kau jangan berbohong," ujar
Shizuka, masuk kembali ke kamar itu lagi,
mencari dengan sia-sia di tempat-tempat
yang paling sempit. Kamar itu kosong, tapi
di satu sudut Shizuka menemukan goresan di
balok kayu. Dua buah setengah lingkaran
saling berhadapan, dan di bawahnya ada
lingkaran penuh.
"Dia pergi mencari Maya."
Shizuka berlutut di lantai, berusaha
menenangkan diri. Miki sudah pergi:
menggunakan kemampuan menghilang,
menyelinap melewati Bunta lalu pergi
menuju kotagadis itu dilatih selama
bertahun-tahun untuk melakukan hal seperti.
Tak ada yang bisa ia lakukan untuk gadis itu
saat ini.
Ia duduk lama, merasakan panasnya cuaca
hari ini. Peluh mulai mengalir di sela
payudara dan ketiaknya. Didengarnya para
penjaga saling berseru dengan tidak sabar,
dan menyadari kalau pilihannya semakin
berkurang. Ia tidak bisa menghilang dan
membiarkan Taku tidak diratapi, tapi apakah
ia harus tinggal di Hofu sampai putranya
atau Kikuta memutuskan kematiannya? Tak
ada waktu untuk menghubungi keluarga
Muto dan meminta bantuan merekadan
lagipula, apakah mereka akan menanggapi
karena kini Zenko telah menyatakan diri
sebagai ketua?
Shizuka memanggil para mendiang untuk
memberinya saran: memanggil Shigeru,
Kenji, Kondo dan Taku. Kesedihan dan
keadaan tidak tidur mulai menuntut
bayarannya. Ia merasakan napas dingin
arwah mereka, Doakan kami Oh, doakan
kami.
Benaknya yang kelelahan makin men-
curahkan perhatiannya pada kata-kata ter-
sebut. Ia akan ke biara dan meratapi men-
diang, hingga dirinya menjadi salah satu dari
mereka, atau mereka akan mengatakan apa
yang harus ia lakukan.
"Bunta," panggilnya. "Ada satu tugas
terakhir yang kuminta kau lakukan. Pergi
dan carikan gunting tajam dan jubah putih
untukku."
Bunta muncul di teras, wajahnya pucat
karena kaget.
"Apa yang terjadi? Jangan katakan kalau
kau ingin menghabisi nyawamu sendiri."
"Sudahlah, lakukan saja permintaanku.
Aku harus ke biara dan mengurus nisan serta
ritual pemakaman Taku. Setelah memenuhi
permintaanku, kubebaskan kau dari ke-
wajibanmu untuk melayaniku."
Sewaktu Bunta kembali, Shizuka me-
nyuruhnya menunggu di luar. Dibukanya
bungkusan itu lalu mengeluarkan gunting.
Dia melepas ikatan rambut, dibagi menjadi
dua untai lalu menggunting keduanya, mem-
baringkan jalinan rambutnya dengan hati-
hati di alas lantai, terkejut memerhatikan
betapa banyak ubannya. Lalu diguntingnya
sisa rambutnya sampai pendek, merasakan
helaiannya berjatuhan di sekelilingnya bak
debu beterbangan. Dibuangnya sisa-sisa
potongan rambut lalu mengenakan jubah
putih. Diambilnya senjata miliknya
pedang, pisau, garotte, serta pisau lempar-
lalu menaruhnya di lantai, di antara dua
untaian rambut panjangnya. Membungkuk
hingga ke lantai, menghaturkan terima kasih
kepada semua senjata dan kepada hidupnya
sampai saat ini; lalu ia meminta dibawakan
semangkuk teh, meminumnya lalu me-
mecahkan cangkir kosong menjadi dua
dengan gerakan cepat.
"Aku takkan minum lagi," ujarnya
lantang.
"Shizuka!" prates Bunta dari teras, tapi
Shizuka tidak mengacuhkannya.
"Apakah dia sudah tidak waras?"
didengarnya putra Bunta berbisik.
"Perempuan yang malang!"
Berjalan dengan perlahan dan berhati-hati,
Shizuka sampai ke bagian depan penginapan.
Sekerumunan kecil orang berkumpul di sini.
Ketika ia melangkah masuk ke dalam tandu,
mereka mengikutinya sampai ke jalan di tepi
sungai menuju Daifukuji. Para pengawal
Zenko dibuat gelisah dengan arak-arakan ini,
dan berusaha menghalau, namun jumlahnya
justru semakin besar dan makin sulit
dikendalikan serta makin tidak bersahabat;
banyak yang berlarian ke sungai yang hampir
kering, dan mengorek batu-batu dari
endapan lumpur lalu melempamya ke arah
pengawal, berhasil menghalau mereka
menjauh dari ger-bang biara. Pemanggul
tandu menurunkan Shizuka di luar gerbang,
dan ia berjalan perlahan memasuki pelataran
utama, bergerak seolah mengambang.
Kerumunan kian banyak di pintu masuk.
Shizuka duduk di tanah, kakinya dilipai bak
makhluk suci di atas bunga teratai, dan
akhirnya ia membiarkan dirinya menangisi
kematian putranya dan pengkhianatan putra-
nya yang satu lagi.
Ritual pemakaman diadakan selagi
Shizuka duduk di sana, dan batu nisan
dipahat lalu didirikan. Hari-hari berlalu dan
Shizuka tetap bergeming, juga tidak makan
dan minum. Di malam ketiga hujan turun
rintik-rintik, dan orang-orang mengatakan
bahwa Surga tengah memberinya minum.
Setelah itu hujan turun setiap malam; di
siang hari sering terlihat burung-burung
beterbangan di sekitar kepalanya.
"Mereka memberinya makan dengan
butiran gandum dan madu," para biarawan
mengumumkan.
Penduduk kota mengatakan kalau Surga
menangisi ibu yang ditinggalkan, dan mereka
bersyukur terhindar dari kekeringan.
Popularitas Zenko sedikit demi sedikit ber-
kurang saat bulan dari bulan kelima mulai
mendekati puncak purnamanya.*
Selama berhari-hari Maya meratapi kepergi-
an kuda-kudanya, tak sanggup membayang-
kan kehilangan yang lebih besar lagi. Shigeko
telah memintanya untuk merawat kedua
kuda itu, dan ia membiarkannya pergi.
Diingat-ingatnya lagi sewaktu melepas tali
kekang dan kedua kuda betina kabur. la
menyesali ketidakmampuan dirinya untuk
bergerak atau membela diri yang tak bisa
dijelaskan. Saat itu ketiga kalinya ia meng-
hadapi bahaya yang sesungguhnyasetelah
serangan di Inuyama dan pertemuan dengan
ayahnyadan merasakan kalau saat itu ia
merasa gagal, walau sudah berlatih selama
bertahun-tahun di Tribe.
Maya punya banyak waktu untuk
merenungkan kegagalannya. Saat tersadar
kembali, tenggorokannya terasa kering,
perutnya mual. Ia sadar sedang berada di
kamar kecil remang-remang, ruang rahasia
rumah Tribe. Takeo sering menceritakan saat
Tribe mengurungnya di kamar semacam ini,
dan kini kenangan itu menghibur dan me-
nenangkannya. Ia mengira Akio akan
langsung membunuhnya, tapi ternyata
tidaklaki-laki itu menahan dirinya untuk
tujuan tertentu. Maya tahu ia bisa kabur
kapan saja karena pintu dan dinding takkan
mampu menahan si kucing, tapi ia masih
belum ingin pergi. Ia ingin tetap dekat
dengan Akio dan Hisao: tak dibiarkannya
mereka membunuh ayahnya; dirinya yang
akan membunuh mereka lebih dulu. Maka
dikendalikan amarah dan rasa takutnya, dan
bersiap mencari tahu semua tentang mereka.
Ia melihat Akio ketika orang itu mem-
bawakan makanan dan minuman; makanan-
nya jarang datang tapi ia tak terganggu
dengan rasa lapar. Maya akhirnya memahami
kalau makin sedikit ia makan, makin mudah
menggunakan kemampuan menghilang dan
sosok kedua. Ia mempraktikkannya saat
sedang sendiri, terkadang bahkan ia pun
terkecoh dan melihat Miki sedang bersandar
di dinding di seberangnya. Ia tidak bicara
pada Akio tapi mengamati, seperti Akio
mengamati dirinya. Maya tahu kalau Akio
tidak memiliki kemampuan menghilang atau
tatapan maut Kikuta, tapi laki-laki itu bisa
melihat orang yang menggunakan kemampu-
an menghilang dan menghindari tatapan
maut. Gerak refleksnya sangat cepat
ayahnya sering bilang kalau itu gerakan
paling cepat yang pernah adasangat kuat
dan tidak punya perasaan.
Dua atau tiga kali sehari, pelayan
perempuan datang untuk mengantarnya ke
kakus: selain itu ia tidak melihat ada orang
lain lagi. Tapi setelah dikurung selama kira-
kira seminggu, di satu malam laki-laki itu
datang, berlutut di depannya lalu meraih dan
membalik telapak tangannya. Maya bisa
mencium bau sake di napasnya, dan cara
bicaranya pelan tapi aneh.
"Kuharap kau jawab pertanyaanku dengan
jujur karena aku adalah ketua keluargamu:
apakah kau memiliki kemampuan seperti
ayahmu?"
Maya menggeleng, dan sebelum selesai
menggeleng dirasakan kepalanya terhempas
dan pandangan matanya kabur selagi Akio
menamparnya. Ia tidak melihat gerakan
tangan laki-laki itu.
"Kau pernah mencoba mengunci tatapan
mataku: kau pasti memiliki bakat tatapan
maut Kikuta. Bagaimana dengan kemampu-
an menghilang?"
Maya menceritakan karena tidak ingin
Akio membunuhnya saat itu juga, tapi tidak
menceritakan tentang si kucing.
"Lalu di mana adikmu?"
"Aku tidak tahu."
Bahkan meski sudah menduganya kali ini,
Maya tidak bisa bergerak cukup cepat untuk
menghindari tamparan yang kedua. Akio
menyeringai, seolah ini permainan yang
sangat dinikmatinya.
"Dia di Kagemura, bersama keluarga
Muto."
"Benarkah? Tapi dia bukan Muto; dia
Kikuta. Kupikir sebaiknya dia berada di sini
bersama kita."
"Keluarga Muto takkan menyerahkan
adikku padamu," sahut Maya.
"Ada perubahan dalam keluarga Muto;
kukira kau sudah tahu. Tribe selalu bersatu
pada akhirnya," ujar Akio. "Begitulah cara
kami bisa bertahan."
Akio mengetuk-ngetuk gigi dengan kuku.
Di bagian belakang tangan kanannya ada
bekas luka lama, melintang dari pergelangan
sampai ke bagian bawah ibu jarinya.
"Kau melihatku membunuh penyihir
Muto itu, Sada. Aku takkan ragu melakukan
yang sama padamu."
Maya tidak bereaksi atas perkataan itu; ia
lebih tertarik pada reaksinya sendiri, ter-
cengang kalau ternyata ia tidak takut pada
laki-laki itu. Ia tak menyadari kalau ternyata,
seperti ayahnya, ia dianugerahi kemampuan
untuk tidak takut pada Kikuta.
"Ini yang pernah kudengar," ujarnya.
"Kalau ibumu takkan melakukan apa-apa
untuk menyelamatkanmu, tapi ayahmu
menyayangimu."
"Itu tidak benar," Maya berbohong.
"Ayahku tidak memedulikan aku dan adikku.
Para ksatria membenci anak kembar dan
menganggap mereka memalukan. Ayahku
hanya bersifat baik, itu saja."
"Dia berhati lembut," ujar Akio, dan
Maya melihat kebencian serta rasa iri pada
Takeo. "Mungkin kau bisa membawa Takeo
kepadaku."
"Hanya untuk membunuhmu," sahut
Maya.
Akio tertawa lalu berdiri. "Tapi dia takkan
membunuh Hisao!"
Maya menemukan dirinya memikirkan
tentang Hisao. Selama setengah tahun ini ia
harus menerima kenyataan kalau ini adalah
putra ayahnya, kakak tirinya, yang tak
pernah dibicarakan siapa pun, tak pernah
diberitahukan pada ibunya. Dan Maya yakin
kalau Hisao tak tahu ayah kandungnya. Ia
memanggil Akio Ayah; Hisao menatap
dengan pandangan tak mengerti ketika ia
mengatakan kalau ia adalah adiknya. Maya
mendengar di benaknya berulang kali suara
Sada, Jadi anak itu benar-benar putra Takeo?
Dan jawaban Taku, Ya, dan menurut
ramalan dialah satu-satunya orang yang bisa
membawa kematian Takeo.
Karakter tidak mengenal kompromi,
semacam warisan Kikuta yang membulatkan
tekadnya yang kejam mulai terbentuk.
Keseimbangan baginya menjadi begitu
sederhana: bila Hisao mati maka Takeo bisa
hidup selamanya.
Selain latihan gerak badan yang dilakukan-
nya dengan tekun, ia tidak ada kesibukan
lain, dan sering terombang-ambing antara
sadar dan tidur, bermimpi bagaikan nyata. Ia
memimpikan Miki, mimpi yang begitu jelas
sehingga ia seperti yakin kalau Miki ada di
kamar itu bersamanya; ia memimpikan
Hisao. Ia berlutut di sampingnya saat
pemuda itu tidur lalu berbisik di telinganya,
"Aku adikmu." Ia bahkan pernah bermimpi
si kucing berbaring di sisi Hisao, dan
merasakan kehangatan tubuh kakaknya itu.
Ia menjadi terobsesi pada Hisao, ingin
tahu semua tentang pemuda itu. Mulai ber-
eksperimen dengan mengambil alih bentuk si
kucing di malam hari selagi tidur. Awalnya ia
ragu, karena hal itu ingin ia sembunyikan
dari Akio, namun lama kelamaan kepercaya-
an dirinya makin meningkat. Di siang hari ia
adalah tawanan, sementara di malam hari ia
bisa keluyuran dengan bebas ke seluruh
bagian rumah, mengamati penghuninya,
serta memasuki mimpi-mimpi mereka.
Dilihatnya dengan sikap remeh rasa takut
dan harapan mereka. Para pelayan
perempuan mengeluhkan adanya hantu,
merasakan hembusan napas di wajah mereka
atau bulu hangat berbaring di sebelah
mereka, mendengar langkah pelan makhluk
besar. Hal-hal aneh terjadi di seluruh kota,
pertanda serta penampakan.
Akio dan Hisao tidur terpisah dari peng-
huni laki-laki lainnya, di kamar bagian
belakang rumah. Maya berjalan pada waktu
tersunyi, tepat sebelum fajar menyingsing
untuk mengamati Hisao yang sedang tidur,
kadang dalam pelukan Akio, kadang sendiri.
Pemuda itu tidur gelisah, bergoyang-goyang
dan bergumam. Mimpi-mimpinya kejam dan
tidak beraturan, tapi itu justru membuat
Maya tertarik. Kadang Hisao terbangun dan
tidak bisa tidur lagi; kemudian pergi ke
rumah kecil di belakang rumah, di sisi lain
halaman, tempat bengkel penempaan dan
perbaikan alat-alat rumah tangga dan senjata.
Maya mengikuti dan mengamatinya, memer-
hatikan gerakannya yang berhari-hari dan
sangat teliti.
Para pelayan perempuan tak pernah meng-
ajak bicara. Selain perjalanan ke kakus ia
hampir tidak pernah bertemu mereka sampai
suatu hari seorang perempuan muda datang
membawakan makanan.
Usianya kira-kira sebaya dengan Shigeko,
dan dia menatap Maya dengan keingin-
tahuan yang terang-terangan.
Maya berkata, "Jangan menatapku. Kau
tahu kalau aku sangat kuat."
Gadis itu tertawa cekikikan tapi tidak
memalingkan wajah. "Kau seperti anak laki-
laki," ujarnya.
"Kau tahu aku anak perempuan," bentak
Maya. "Kau pernah mengintipku kencing
ya?" Maya bicara dengan bahasa anak laki-
laki, dan gadis itu tertawa.
"Siapa namamu?" tanya Maya.
"Noriko," bisiknya.
"Noriko, akan kubuktikan betapa kuatnya
diriku. Kau bermimpi tentang kain pem-
bungkus: kau pernah membungkus beberapa
kue mochi dengairkain itu dan saat kau buka
bungkusannya, kue-kue itu penuh ulat."
"Aku tidak bilang siapa-siapa!" gadis itu
tercekat, tapi malah mendekati Maya.
"Bagaimana kau bisa tahu?"
"Aku tahu banyak hal," sahut Maya.
"Tatap mataku." Ditahannya tatapan gadis
itu selama beberapa saat, cukup lama untuk
melihat kalau gadis itu percaya pada
takhayul, dan satu lagi, sesuatu tentang
Hisao....
Kepala gadis itu berputar saat Maya
menarik kekuatan tatapan mautnya. Maya
menampar kedua pipi gadis itu untuk
menyadarkannya. Noriko menatap bingung.
"Kau bodoh kalau mencintai Hisao," ujar
Maya terus terang.
Gadis itu tersipu. "Aku kasihan padanya,"
bisiknya. "Ayahnya sangat keras kepadanya,
dan dia sering sakit."
"Sakit yang bagaimana?"
"Dia sering terserang sakit kepala yang
parah. Muntah, dan pandangannya kabur.
Hari ini dia sedang sakit. Ketua Kikuta
sangat marah karena mereka seharusnya pergi
menemui Lord ZenkoAkio akhirnya pergi
sendiri."
"Mungkin aku bisa menolongnya," kata
Maya. "Kenapa kau tidak mengantarku
kepadanya?"
'Tidak bisa! Akio akan membunuhku
kalau dia tahu."
"Antar aku ke kakus," ujar Maya. "Tutup
pintunya, tapi jangan dikunci. Aku akan ke
kamar Hisao. Jangan khawatir; takkan ada
orang yang melihatku. Tapi kau harus
berhati-hati kalau Akio datang. Peringatkan
aku saat dia kembali."
"Kau takkan menyakiti Hisao?"
"Dia laki-laki dewasa. Aku baru empat
belas tahunbahkan masih anak-anak. Aku
tidak punya senjata. Bagaimana bisa aku
menyakitinya? Lagipula, sudah kukatakan
kalau aku ingin menolongnya."
Bahkan saai bicara, Maya ingat semua cara
yang pernah diajarkan kepadanya untuk
membunuh dengan tangan kosong. Lidahnya
menjilati bibir; tenggorokannya terasa kering,
tapi setain itu ia tenang-tenang saja. Hisao
sedang sakit, lemah, mungkin pandangannya
kabur karena penyakitnya. Dia akan mudah
dilumpuhkan dengan tatapan maut; di-
sentuhnya lehernya sendiri, meraba. urat
nadinya, membayangkan urat nadi Hisao.
Dan kalau cara itu gagal, ia akan memanggil
si kucing....
"Ayo, Noriko, kita ke kamar Hisao. Dia
membutuhkan bantuanmu." Ketika Noriko
masih ragu, Maya berkata pelan, "Dia juga
mencintaimu."
"Benarkah?" mata gadis itu berbinar-binar
di wajahnya yang kurus dan pucat.
"Dia tidak bilang siapa-siapa, tapi dia
memimpikan dirimu. Aku pernah melihat
mimpinya dengan cara yang sama aku
melihat mimpimu. Dia memimpikan dirinya
memelukmu dan mengigau dalam tidurnya."
Maya memerhatikan wajah Noriko men-
jadi lembut; tidak suka pada gadis itu karena
mabuk kepayang oleh cinta. Noriko meng-
geser pintu terbuka, melihat ke luar dan
memberi isyarat kepada Maya. Mereka ber-
jalan cepat-cepat ke belakang rumah, dan di
pintu kakus Maya meremas perutnya dan
berteriak seolah kesakitan.
"Cepat, dan jangan berlama-lama di dalam
situ," ujar Noriko, dengan spontan.
"Mana bisa kutahan kalau sakit begini?"
sahut Maya dengan nada yang sama. "Ini
gara-gara makanan menjijikkan yang kau
bawa!"
Disentuhnya bahu Noriko saat bentuk
tubuhnya memudar. Noriko sudah terbiasa
dengan keanehan semacam itu, mengarahkan
pandangannya tetap ke depan. Maya ber-
gegas pergi ke kamar Hisao tidur, menggeser
pintunya terbuka, lalu melangkah masuk.
Teriknya sinar matahari di luar telah
mengecilkan pupil matanya, dan sesaat ia tak
bisa melihat apa-apa. Kamar itu baunya
masam, samar-samar tercium bau muntah.
Kemudian dilihatnya pemuda itu meringkuk
di matras di sudut, satu tangannya menutupi
wajah. Dari irama napasnya yang teratur
sepertinya dia memang tidur. Ia tak akan
mendapat kesempatan seperti ini lagi. Sambil
menahan napas, ia melenturkan pergelangan
tangan, mengumpulkan tenaga, berjalan
melintasi kamar, berlutut di sebelah Hisao
dan menyerang bagian lehernya
Usahanya melemahkan konsentrasinya
hingga kemampuan menghilangnya sirna.
Mata Hisao terbuka, dan menatap sejenak
sebelum berkelit dari cengkeraman tangan
gadis itu. Pemuda itu lebih kuat dari
perkiraan, tapi ia langsung menatap mata
pemuda itu dan selama beberapa saat
membuat Hisao pusing; cengkeraman jarinya
makin kuat bak tentakel, dan selagi
punggung Hisao melengkung dan memukul-
mukul saat meronta berusaha melepaskan
diri. Ia bergantung seperti hewan saat Hisao
berusaha bangkit dengan tangan dan lutut.
Kulit pemuda itu berkeringat, dan Maya
merasakan cengkeramannya mulai terasa
licin. Hisao juga merasakannya, lalu
mengibaskan kepala saat mencoba berkelit
lagi. Ditangkapnya tubuh Maya lalu
dihempaskannya ke dinding. Layar kasa yang
rapuh sobek, dan dari suatu tempat ia
mendengar Noriko memanggil namanya.
Aku gagal, pikirnya, selagi tangan Hisao
mencengkcram lehernya, dan Maya bersiap
untuk mati.
Miki! Ujarnya pelan, dan seolah Miki
mendengarnya, dirasakannya kemarahan
Miki pada Hisao merasuki dirinya dan si
kucing mulai muncul, meludah dan meng-
geram. Hisao berteriak kaget dan
melepasnya; si kucing bergerak mundur, siap
melarikan diri tapi masih belum ingin
menyerah."
Waktu sejenak itu memberi Maya waktu
untuk meraih kembali kendali diri dan
konsentrasinya. Dilihatnya kalau ternyata ada
sesuatu yang melemahkan Hisao. Mata
pemuda itu tidak tokus; agak terhuyung-
huyung. Sepeninya pemuda itu berusaha
melihat sesuatu di belakang Maya, dan
mendengarkan suara berbisik.
Maya mengira itu semacam tipuan untuk
mengecohkan pandangannya, maka ia terus
menatap tajam pemuda itu. Bau busuk dan
jamur semakin menyengat: kamar itu terasa
panas tak tertahankan: bulu si kucing
menyesakkan napasnya. Terdengar olehnya
bisikan di sebelah kanannya; kendati tak
memahami kata-kata itu. tapi ia tahu kalau
itu bukan suara Noriko. Ada orang lain lagi
di kamar itu.
Maya menoleh ke samping dan melihat
perempuan itu. Masih muda, mungkin
sembilan belas atau dua puluh tahun,
potongan rambutnya pendek, wajahnya
pucat. Perempuan itu mengenakan jubah
putih, menyeberangi sisi seberang dunia fana,
dan tubuhnya melayang. Ekspresi di wajah-
nya melukiskan kemarahan dan putus asa
yang bahkan membuat hati Maya terharu.
Dilihatnya kalau Hisao begitu ingin menatap
hantu itu tapi juga takut; roh si kucing yang
merasuki dirinya bergerak dengan bebas
antara dua dunia.
Jadi ini yang dimaksud Taku, renungnya
saat menyadari hutang budinya pada si
kucing dan bagaimana ia bisa memenuhinya.
Dan kemudian ia menyadari kekuatan yang
ini dan bagaimana ia bisa memanfaatkannya.
Perempuan itu berseru memanggilnya,
"Tolong aku! Tolong aku!"
"Apa yang kau inginkan?" tanya si kucing.
"Aku ingin putraku mendengarkan aku!"
Belum sempat Maya menjawab, Hisao
mendekat.
"Kembali kau!" ujar Hisao. "Kau telah
memaafkanku. Kemarilah, ijinkan aku
menyentuhmu. Apakah kau hantu juga?
Boleh aku menyentuhmu?"
Ia melihat perubahan tangan Hisao saat
menggapai. Tangan itu melembut berbentuk
melengkung yang ingin sekali mengelus bulu
si kucing. Ia terkejut, si kucing bereaksi
seolah tunduk pada majikannya, menunduk-
kan kepala serta merebahkan telinga, dan
membiarkan Hisao membelainya.
Ia mematuhi keinginan si kucing.
Sentuhan Hisao menyatukan sesuatu di
dalam diri mereka. Hisao tercekat. Ia merasa-
kan penderitaan saudaranya itu seolah berada
di kepalanya sendiri: lalu berkurang. Maya
melihat, melalui mata Hisao: pandangan
setengah buta, kumparan cahaya bak roda
bergerigi dari alat penyiksaan, dan Hisao ber-
kata, "Ibu?"
Hantu itu bicara. "Akhirnya!" ujarnya.
"Sekarang maukah kau mendengarkan Ibu?"
Tangan Hisao masih di atas kepala si
kucing. Maya merasakan kebingungan
pemuda itu: rasa lega karena penderitaannya
telah sirna, rasa takutnya memasuki dunia
alam baka, rasa takut melihat sedikit
kekuatan yang bangkit. Di tepi kesadaran
Maya, bergelayut ketakutan yang sama, jalan
yang terbentang ke depan yang tak ingin ia
ambil, jalan yang dirinya dan Hisao harus
lalui bersama, meski ia membenci pemuda
itu dan ingin membunuhnya.
Noriko memanggil-manggil dari luar.
"Cepat! Ketua sudah datang!"
Hisao mengangkat tangannya. Maya
kembali ke wujud aslinya dengan rasa lega. Ia
ingin pergi dari pemuda itu, tapi Hisao
menangkap lengannya; ia bisa merasakan
cengkraman Hisao sampai ke tulang
sumsumnya. Pemuda itu tengah menatap-
nya, tatapannya kagum dan lapar.
"Jangan pergi," ujarnya. "Katakan padaku.
Apakah kau melihatnya?"
Noriko, berdiri di teras, berganti-ganti
memandang kedua orang. "kau sudah
baikan," serunya. "Gadis itu menyembuh-
kanmu!"
Mereka berdua tidak mengacuhkannya.
"Tentu saja aku melihatnya," sahut Maya
seraya menyelinap melewati Hisao. "Dia itu
ibumu, dan dia ingin agar kau mendengar-
kannya."*
Dia akan bilang pada Akio, pikir Maya, selagi
Noriko bergegas kembali ke kamar yang
terkunci. Dia akan ceritakan semuanya. Akio
akan tahu tentang si kucing. Entah dia akan
membunuhku atau mereka akan memanfaat-
kan aku untuk melawan Ayah. Aku harus
melarikan dirinya, aku harus pulang; aku akan
memperingatkan Ibu tentang Zenko dan
Hana. Aku harus pulang.
Tapi sentuhan tangan majikannya mem-
buat si kucing enggan pergi. Dan Maya
ingin, bertentangan dengan keputusannya,
berjalan di antara dua dunia dan berbicara
dengan hantu. Ia ingin tahu apa yang mereka
ketahui, bagaimana rasanya mati, serta semua
rahasia lain yang disimpan orang mati dari
mereka yang masih hidup.
Maya tidur nyenyak selama berminggu-
minggu, tapi segera setelah kembali ke kamar
sempit, kelelahan yang menggiurkan menye-
limuti dirinya. Kelopak matanya terasa
makin berat; sekujur tubuhnya terasa sakit
karena kelelahan. Tanpa bicara kepada
Noriko, ia berbaring di lantai dan langsung
tertidur lelap.
Maya terbangun, seolah ditarik paksa
keluar dari air, oleh sebuah perintah.
Datanglah kepadaku.
Kala itu malam gelap pekat, udara terasa
lembap. Leher dan rambutnya terasa lembap
karena keringat. Ia tak ingin merasakan bulu
tebal si kucing. tapi majikannya memanggil-
nya: si kucing harus menemuinya.
Telinga si kucing berdiri tegak; kepalanya
berputar. Kucing itu berjalan dengan mudah-
nya melewati layar kasa dan dinding menuju
bengkel tempat api penempaan menyala
semalaman. Para penghuni rumah sudah
terbiasa melihat Hisao berada di situ saat dini
hari. Pemuda itu telah menemukan tempat
yang cocok dan tidak ada orang yang meng-
ganggunya.
Hisao menggapaikan tangan dan kucing
itu menghampiri, seolah merindukan
sentuhan dan belaiannya. Pemuda itu
membelai, dan si kucing menjilati pipinya
dengan lidah kasarnya. Tak satu pun dari
keduanya bicara, tapi di antara mereka
mengalir kerinduan akan kedekatan serta
sentuhan kasih sayang yang dibutuhkan
hewan itu.
Setelah agak lama, Hisao berkata,
"Perlihatkan wujud aslimu."
Maya tersadar kalau ia berdempetan
dengan Hisao, tangan pemuda itu masih di
tengkuknya. Rasanya menyenangkan se-
kaligus menjijikkan. Ia melepaskan diri dari
pelukan Hisao. Tidak bisa dilihatnya ekspresi
wajah Hisao dalam keremangan cahaya. Bara
api meretih, asap membuat matanya pedih.
Hisao mengangkat lentera lalu menatap. Ia
terus menunduk, tak ingin menentang
tatapan pemuda itu. Tak satu pun dari
mereka bicara, seakan tak ingin kembali ke
dunia manusia yang penuh dengan kata-kata.
Akhirnya Hisao berkata, "Mengapa kau
datang sebagai kucing?"
"Aku membunuh seekor kucing dengan
tatapan maut Kikuta, dan rohnya merasuki
diriku," sahutnya. "Tak seorang Muto pun
tahu bagaimana menghadapinya, tapi Taku
telah membantuku mengendalikannya."
"Aku adalah penguasanya: tapi aku tak
tahu sebabnya atau bagaimana caranya.
Kucing itu mengurangi sakitku, saat ber-
samaku, dan menenangkan suara-suara
hingga aku bisa mendengarnya. Aku suka
kucing, tapi ayahku pernah membunuh
seekor kucing di depan mataku karena aku
menyukainyakau bukan kucing itu kan?"
Maya menggeleng.
"Aku tetap menyukaimu," ujarnya. "Aku
pasti sangat menyukaimu; aku tidak bisa
berhenti memikirkanmu. Aku memerlukan
dirimu bersamaku. Berjanjilah kau akan
tinggal bersamaku."
Hisao meletakkan lentera kembali di atas
lantai dan berusaha menarik tubuh Maya
lebih dekat lagi. Maya menolaknya.
"Kau tahu kalau kita bersaudara?"
tanyanya.
Wajah Hisao mengkerut. "Dia itu ibumu?
Hantu perempuan itu? Itukah sebabnya kau
bisa melihatnya?"
"Bukan, ibu kita berbeda, tapi ayah kita
sama."
Kini Maya bisa melihatnya dengan lebih
jelas. Hisao tidak mirip ayahnya, atau
dengannya atau Miki, namun rambutnya
yang mengkilap mirip dengan rambut
mereka, dan kulitnya memiliki tekstur dan
warna yang sama, dengan nuansa warna
madu. Seketika Maya teringat kenangan akan
masa kecilnyapayung pelindung sinar
matahari dan cairan unluk membuat kulit
lebih terang: betapa bodoh dan sia-sianya
semua itu sekarang.
"Ayahmu adalah Otori Takeo, yang kami
sebut si Anjing," Hisao tertawa dengan
seringai yang dibenci Maya. Tiba-tiba ia
membenci pemuda itu lagi, dan merasa jijik
pada dirinya sendiri atas keinginan dan
ketentraman yang dirasakan kucing itu
hingga tunduk pada Hisao. "Aku dan ayahku
akan membunuhnya."
Hisao menjauh, menjauh dari cahaya
lentera, dan mengeluarkan senjata api kecil.
Cahaya berkilat di laras baja hitam senjata
itu. "Dia itu penyihir, dan tidak seorang pun
berhasil mendekatinya, tapi senjata ini lebih
kuat ketimbang ilmu sihir." Takeo melirik ke
arah Maya, lalu berkata dengan nada kejam
yang disengaja, "Kau sudah lihat bagaimana
senjata ini menghabisi Muto Taku."
Maya tidak menjawab, tapi melihat
dengan jelas dan tanpa perasaan terharu pada
kematian Taku. Laki-laki itu mati dalam
pertarungan, penuh kehormatan; tidak
mengkhianati siapa pun; Taku dan Sada mati
bersama. Tidak ada yang harus disesali dari
kematiannya. Umpan Hisao tak membuat-
nya terpancing maupun melemahkan diri-
nya.
"Lord Otori adalah ayahmu," ujar Maya.
"Itu sebabnya aku berusaha membunuhmu,
agar kau tidak membunuh ayahmu sendiri."
"Akio adalah ayahku." Keraguan dan
kemarahan terdengar dalam suaranya.
"Akio memperlakukanmu dengan kejam,
menganiaya dan berbohong padamu. Dia
bukan ayahmu. Kau tidak tahu bagaimana
seharusnya sikap ayah pada anaknya."
"Dia sayang padaku," bisik Hisao. "Dia
menyembunyikannya dari semua orang, tapi
aku tahu. Dia membutuhkan diriku."
"Tanya pada ibumu," sahut Maya.
"Bukankah sudah kukatakan padamu untuk
mendengarkannya? Ibumu akan mengatakan
yang sebenarnya kepadamu."
Kemudian keadaan hening dalam waktu
lama. Udara terasa panas: Maya bisa
merasakan peluh di dahinya. Ia merasa
kehausan.
"Jadilah kucing lagi, maka aku akan
mendengarkannya," katanya begitu pelan
hingga Maya hampir tidak bisa mendengar
suaranya.
"Apakah ibumu ada di sini?"
"Dia selalu ada di sini," sahut Hisao. "Dia
terikat pada diriku oleh seutas tali, seperti
dulu aku pernah terikat pada tubuhnya. Aku
tak pernah terbebas darinya. Kadang dia
diam saja. Itu tidak terlalu buruk. Saat dia
ingin bicaramaka rasa sakit itu menyerang-
ku."
"Karena kau berusaha melawan dunia
arwah," ujar Maya. "Hal yang sama terjadi
padaku. Saat si kucing ingin muncul dan aku
menolaknya, aku juga kesakitan."
Hisao berkata, "Aku tidak memiliki
kemampuan Tribe apa pun. Aku tidak
seperti kau. Aku tidak bisa menggunakan
kemampuan menghilang. Aku tidak bisa
menggunakan sosok kedua. Bahkan melihat
semua kemampuan ini pun membuat
perutku agak mual. Tapi tidak begitu dengan
si kucing. Dia membuatku nyaman dan
kuat."
Hisao tidak menyadari kalau suaranya
berubah dan menjadi seperti hipnotis, dihiasi
dengan daya tarik yang tak bisa ditolak
Maya. Gadis itu merasakan tubuh si kucing
meregang dan melentur dengan keinginan
yang kuat. Hisao menarik tubuh si kucing
yang lentur itu lebih mendekat dan
membelai-belai bulu-bulu tebalnya.
"Tetaplah di dekatku." bisiknya, dan
kemudian, bicara lebih keras, "Aku akan
mendengarkan, apa pun yang ingin kau
katakan."
Bara api penempaan dan cahaya lentera
meredup dan berkelap-kelip saat angin
hangat dan berbau busuk tiba-tiba ber-
hembus meniup debu di lantai, meng-
gerakkan debu dan membuat daun jendela
bergemeretak. Kemudian api makin ber-
kobar, membara makin terang, menerangi
arwah perempuan saat mendekat, melayang.
Hisao duduk diam tak bergerak; si kucing
berbaring di sebelahnya dengan kepala di
bawah tangan Hisao, matanya yang
keemasan tidak berkedip.
"Nak," kata sang ibu, suaranya gemetar.
"Biarkan Ibu menyentuhmu, biarkan ibu
memelukmu." Jemari kurusnya menyentuh
dahi Hisao, membelai rambutnya, dan Hisao
merasakan sosok tubuh ibunya begitu dekat,
merasakan tekanan paling lemah saat ibunya
memeluk dirinya.
"Dulu Ibu suka memelukmu seperti ini
saat kau bayi."
"Aku ingat," bisiknya.
"Ibu tak sanggup meninggalkanmu.
Mereka, Kotaro dan Akio, memaksa Ibu
minum racun. Mereka menangisi kepergian
Ibu dengan cinta, setelah mematuhi perintah
Ketua dan memasukkan dengan paksa pit
beracun ke mulut Ibu. Mereka menyaksikan
Ibu mati dengan jiwa dan raga yang
menderita. Tapi mereka tidak memisahkan
diri Ibu darimu. Kala itu usia Ibu baru dua
puluh tahun. Ibu tak ingin mati. Akio mem-
bunuh Ibu karena dia membenci ayahmu.
Tangan Hisao menggosok-gosok bulu si
kucing, membuat hewan itu menunjukkan
cakarnya. "Siapakah ayahku?"
"Gadis itu benar. Dia memang adikmu;
Takeo adalah ayah kandungmu. Ibu
mencintainya. Mereka memerintahkan Ibu
agar tidur dengannya, agar Ibu mengandung
dirinya. Ibu mematuhi mereka. Tapi mereka
tak menyangka kalau Ibu akan mencintainya,
dan kalau kau akan dilahirkan hasil dari
cinta. Mereka berusaha menghancurkan kita
semua. Pertama Ibu; kini mereka akan
memanfaatkan dirimu untuk membunuh
ayah kandungmu, lalu kau pun akan mati."
"Bohong," sahutnya, tenggorokannya ter-
cekat.
"Ibu sudah mati," sahutnya. "Hanya orang
hidup yang berbohong."
"Aku membenci si Anjing seumur hidup-
ku; aku tidak bisa mengubahnya sekarang."
"Kau tidak mengenal siapa dirimu? Tak
ada lagi orang Tribe, dari lima keluarga, yang
bisa mengenali dirimu. Ibu akan ceritakan
apa yang dikatakan kakekmu saat kematian-
nya. Kau adalah penguasa alam baka."
***
Lama setelah kejadian itu, ketika kembali ke
kamarnya dan berbaring terjaga,
memandangi kegelapan yang pucat perlahan
berubah terang, Maya mengingat-ingat
kembali saat mendengar si arwah meng-
ucapkan semua kata-kata ini: tengkuknya
bergidik; bulu-bulunya tegak berdiri. Tangan
Hisao memegang erai lehernya. Hisao belum
sepenuhnya memahaminya, tapi Maya ingat
kata-kata Taku: penguasa alam baka adalah
orang yang bisa berjalan di antara dua dunia,
dukun yang mampu menenangkan atau
menghasut orang yang sudah mati.
Diingatnya suara-suara hantu yang
berdesakan di sekelilingnya pada malam
menjelang Perayaan Oban, di tepi pantai di
depan rumah Akane; dirasakannya penye-
salan atas kematian mereka yang kejam dan
tidak pada waktunya, serta tuntutan mereka
untuk balas dendam. Mereka mencari Hisao,
penguasa mereka, dan dirinya sebagai si
kucing, memberinya kekuatan untuk
menguasai mereka. Tapi bagaimana Hisao,
pemuda yang kejam dan brengsek ini,
memiliki kekuatan semacam itu? Dan
bagaimana Akio bisa memanfaatkan dia bila
tahu itu?
Hisao tak ingin Maya meninggalkannya.
Ia merasakan kuatnya keinginan Hisao itu,
dan ia merasakan keinginan itu memikat
sekaligus berbahaya. Tapi Hisao tak ingin
Akio tahu itu, belum... Ia tidak terlalu
memahami bagaimana perasaan Hisao yang
sebenarnya atas laki-laki yang selalu dipercaya
sebagai ayahnya: gabungan antara cinta dan
kebencian, meremehkan serta iba, juga takut.
Maya mengenali perasaan seperti itu
karena ia merasakan hal yang sama pada
pemuda itu.
Ia tidak tidur, dan sewaktu Noriko
membawakannya nasi dan sop untuk makan
pagi, ia tidak terlalu berselera. Mata Noriko
merah, sepertinya habis menangis.
"Kau harus makan," ujar Noriko. "Dan
setelah itu kau harus bersiap untuk
bepergian."
"Bepergian? Aku akan pergi kemana?"
"Lord Arai akan kembali ke Kumamoto.
Hofu sedang gempar. Muto Shizuka tengah
berpuasa di Daifukuji dan hanya diberi
makan oleh burung." Noriko gemetar.
"Seharusnya aku tidak mengatakan ini. Ketua
harus menemaninya, dan Hisao juga. Mereka
pasti mengajakmu." Matanya penuh dengan
air mata dan disekanya dengan lengan jubah.
"Hisao sudah cukup sehat untuk bepergian.
Seharusnya aku senang."
Bersyukurlah dia akan pergi jauh darimu,
pikir Maya, lalu bertanya, "Shizuka ada di
Hofu?"
"Dia datang untuk memakamkan putra
bungsunya, dan kabarnya dia sudah tidak
waras. Orang-orang menyalahkan Lord Arai -
serta menuduhnya terlibat dalam kematian
Taku. Arai gusar dan segera pulang ke
rumahnya menyiapkan pasukannya untuk
berperang, sebelum Lord Otori kembali dari
Miyako."
"Omong kosong apa yang kau katakan!
Kau tidak tahu apa-apa tentang hal ini!"
Maya menyembunyikan ketakutannya
dengan kemarahan.
"Aku memberitahumu hanya karena kau
sudah menolong Hisao," sahut Noriko. "Aku
takkan mengatakan apa-apa lagi." Gadis itu
mengatupkan bibir rapat-rapat, marah dan
tersinggung.
Maya mengangkat mangkuk sop dan
menghabiskannya, pikirannya berpacu
kencang. Ia tak ingin membiarkan mereka
membawanya ke Kumamoto. Ia tahu kalau
kedua putra Zenko, Sunaomi dan Chikara,
sudah dikirim ke Hagi untuk menjamin
kesetiaan ayah mereka, dan bahwa Zenko
takkan ragu-ragu menekan ayahnya. Hofu
berada di Negara Tengah dan setia pada
Otoriia mengenal kota itu dan tahu jalan
pulang. Sedangkan Kumamoto jauh di
wilayah Barat; ia belum pernah ke sana.
Begitu sampai di sana, ia tidak akan punya
peluang kabur.
"Kapan kami akan pergi?" tanya perlahan.
"Begitu Ketua dan Hisao siap. Kau akan
sudah di jalan sebelum siang. Kudengar Lord
Arai akan mengirim pengawal." Noriko
mengangkat mangkuk. "Aku harus mem-
bawa semua ini ke dapur."
"Aku belum selesai makan."
"Apa itu salahku kalau kau makan begitu
lambat?"
"Lagipula aku juga tidak lapar."
"Kumamoto jauh dari sini," ujar Noriko
saat keluar.
Maya tahu ia hanya punya sedikit waktu
untuk mengambil keputusan. Mereka pasti
membawanya dengan disembunyikan,
dengan tangan terikat mungkin; ia bisa saja
mengecoh pengawal Zenko tapi takkan bisa
lolos dari Akio. Ia mulai mengukur kamar itu
dengan jarak langkah. Udara terasa semakin
panas; ia lapar dan lelah; saat berjalan tanpa
berpikir, ia hanyut dalam mimpi yang
terjaga, dan melihat Miki berada di gang di
belakang rumah. Maya terbangun kaget. Ini
mungkin nyata: Shizuka pasti mengajak Miki
begitu mendengar kematian Taku. Mereka
datang untuk mencarinya. Miki ada di luar.
Mereka bisa pergi ke Hagi bersamasama;
mereka bisa pulang ke rumah.
Ia tidak ingin berpikir lagi karena hanya
akan membuang-buang waktu. Ia mengubah
wujud menjadi kucing dan melewati dinding.
Seorang perempuan di beranda berusaha
menghalaunya dengan sapu sewaktu Maya
berlari melewatinya; terus berlari melintasi
halaman, tidak berusaha sembunyi-
sembunyi, tapi ketika sampai di dinding
sebelah luar, dilewatinya bangunan bengkel
dan merasakan kehadiran Hisao di sana.
Jangan sampai dia mclihatku. Dia tidak
akan membiarkan aku pergi
Gerbang belakang terbuka, dan dari
jalanan di depan-nya terdengar olehnya derap
kuda mendekat. la menoleh ke belakang dan
melihat Hisao berlari dengan senjata di
tangan, matanya mencari-cari di halaman.
Ketika melihat, dia berseru, "Kembali!"
Ia merasakan kekuatan perintah itu, dan
tekadnya melemah. Si kucing mendengarkan
majikannya; si kucing tidak akan meninggal-
kannya. Ia sudah berada di luar, di jalanan,
tapi kaki kucing itu terasa berat. Hisao
memanggil lagi. Ia harus kembali kepadanya.
Maya sadar dari sudut matanya melihat
sosok samar yang tak kelihatan. Secepat bilah
pedang, dari seberang jalan, sesuatu melesat
di antara kucing itu dan Hisao, dan sosok itu
memiliki ketajaman yang luar biasa hingga
memutuskan keterkaitan antara mereka
berdua.
"Maya," didengarnya Miki memanggil.
"Maya!" dan saat itulah Maya mendapatkan
kekuatan untuk berubah wujud. Miki,
sekarang kelihatan, berdiri di sampingnya.
Adik kembarnya itu memegang erat-erat
tangannya. Hisao berteriak dari gerbang, tapi
suaranya hanya suara anak laki-laki. Maya
tidak harus mendengarkannya lagi.
Kedua gadis itu menghilang lagi, dan
selagi pengawal Lord Arai datang dari sudut
jalan, mereka berlari tanpa terlihat memasuki
jalan-jalan kota pelabuhan yang sempit dan
berliku-liku.*
Keberangkatan Takeo dari Miyako dilepas
dengan upacara dan kegembiraan yang lebih
besar, meski ada kekagetan dan kekecewaan
karena ia pergi begitu cepat.
"Kemunculan Anda ibarat komet," ujar
Lord Kono, ketika bangsawan itu datang
mengucapkan selamat jalan. "Melesat ber-
cahaya melintasi langit musim panas."
Takeo ingin tahu seberapa tulus pujian ini,
karena orang biasanya percaya kalau komet
merupakan pertanda buruk datangnya
kehancuran dan kelaparan.
"Kurasa aku ada alasan mendesak untuk
pulang," sahutnya, seraya memikirkan kalau
Kono mungkin sudah tahu apa alasannya;
tapi bangsawan itu tidak menunjukkannya,
atau menyebutkan kematian Taku.
Saga Hideki bahkan lebih tak bisa berkata-
kata karena terkejut dan merasa tidak senang
akan kepergiannya yang mendadak itu.
Mendesak agar tinggal lebih lama lagiatau
jika Lord Otori benar-benar harus kembali ke
Tiga Negara, agar setidaknya meninggalkan
Lady Maruyama untuk menikmati indahnya
musim panas di ibukota.
"Masih banyak yang perlu kita
bicarakanaku ingin tahu cara Anda
memerintah Tiga Negara, apa yang
menopang kemakmuran dan kesejahteraan
kalian, bagaimana cara Anda menghadapi
kaum barbar."
"Kami menyebutnya orang asing," Takeo
berani membetulkan perkataannya.
Saga menaikkan alisnya. "Orang asing,
kaum barbar, sama saja."
"Lord Kono menghabiskan banyak waktu
bersama kami. Dia pasti sudah melapor-
kannya kepada Anda."
"Lord Otori," Saga mencodongkan badan
dan bicara dengan penuh rahasia. "Lord
Kono mendapatkan sebagian besar informasi-
nya dari Arai. Keadaan sudah berubah sejak
saat itu."
"Apakah aku mendapat jaminan dari Lord
Saga?"
"Tentu saja! Kita sudah mengumumkan
kesepakatan yang mengikat. Anda tidak perlu
khawatir. Kita adalah sekutu dan tak lama
akan menjadi kerabat."
Takeo bersikeras menolak bujukannya
dengan sikap sopan yang tegas; dari semua
penjelasan tentang keindahan yang perlu
mereka lihat sebenarnya tidak bagus. Ibukota
dilanda hawa panas, dan hujan plum yang
bisa terjadi kapan saja membuat udara
menjadi lembap dan berjamur. Ia tidak ingin
Shigeko menderita dalam kondisi seperti itu.
Ia ingin sekali pulang, merasakan dingin
angin laut di Hagi, bertemu Kaede dan
putranya, kemudian menghadapi Zenko
dengan tegas.
Lord Saga memberi kehormatan dengan
menemani mereka selama minggu pertama
perjalanan sampai di Sanda, tempat dia
mengatur jamuan makan perpisahan.
Saat jamuan selesai dan mereka akhirnya
mengucapkan selamat tinggal, Takeo merasa
semangatnya bangkit. Ia nyaris tidak men-
duga bisa pulang membawa kemenangan
besar seperti ini. Membawa dukungan dan
pengakuan Kaisar, dan juga persekutuan
yang tulus dengan Saga. Perbatasan wilayah
Timur akan aman dari serangan; tanpa
dukungan Saga, Zenko bisa disembuhkatt
dari ambisinya dan menerima kenyataan
sahnya pemerintahan Takeo.
"Bila ada bukti keterlibatannya dalam
kematian Taku, maka dia akan dihukum.
Tapi bila memungkinkan, demi Shizuka,
maka aku akan membiarkannya tetap
hidup."
Takeo melakukan perjalanan dengan
tandu, dengan formalitas besar, sampai ke
Sanda. Sungguh lega Saga sudah pergi dan
membuatnya bisa menanggalkan jubah
indahnya lalu menunggang Tenba lagi.
Hiroshi yang menungganginya karena kuda
itu menjadi terlalu bersemangat dan sulit
dikendalikan bila tidak ditunggangi setiap
hari; kini Hiroshi menunggang kuda tua
miliknya, Keri, anak Raku.
"Gadis itu, Mai, menceritakan kalau
Ryume, kuda Taku, mati bersama majikan-
nya," tutur Hiroshi kepada Takeo saat
mereka berkuda berdampingan. "Tapi tidak
jelas apakah dia juga mati ditembak."
Hari itu cuaca panas, langit tak berawan;
kuda-kuda berkeringat selagi jalan semakin
menanjak menuju tanah lapang yang masih
kelihatan jauh.
"Aku ingat dengan jelas saat pertama kali
kita lihat kuda-kuda jantan itu," sahut
Takeo. "Kau langsung mengenali kalau
mereka adalah anak-anak Raku. Mereka
adalah pertanda pertama bagiku akan
kembalinya harapan, bahwa kehidupan
senantiasa bermula dari kematian."
"Aku merindukan Ryume hampir sebesar
rinduku pada Taku," ujar Hiroshi pelan.
"Untungnya kuda Otori tidak menunjuk-
kan tanda-tanda kematian. Tentu saja, di
bawah bimbingan tangan ahlimu, kurasa
mereka makin berkembang. Kukira aku tak
akan memiliki kuda seperti Shun lagi, tapi
mesti kuakui aku sangat senang dengan
Tenba."
'Tenba menantang untuk dijinakkan, tapi
ternyata hasilnya baik-baik saja."
Tenba berderap cukup tenang, namun
tepat saat Hiroshi bicara, kuda itu
mengibaskan kepala dan berputar ke arah
mereka datang, seraya meringkik keras.
"Kau terlalu cepat bicara," ujar Takeo,
seraya mengarahkan kuda itu kembali dalam
kendalinya dan memaksanya agar bergerak ke
depan lagi. "Dia masih menjadi tantangan:
kau takkan bisa mengabaikannya."
Shigeko, yang sedari tadi berkuda di akhir
arak-arakan bersama Gemba, datang meng-
hampiri mereka.
"Sesuatu membuatnya kesal," ujar
Shigeko, dan membelokkan pelana untuk
memandang ke arah belakangnya.
"Dia merindukan kirin," ujar Hiroshi.
"Mungkin sebaiknya kita tinggalkan saja
dia bersama kirin," ujat Takeo. "Sempat
terpikir olehku, tapi aku tidak ingin berpisah
dengannya."
"Dia akan menjadi liar dan tidak bisa
dikendalikan di Miyako." Hiroshi melirik ke
arah Shigeko. Tenba dijinakkan dengan
kelembutan; kini tidak bisa ditangani dengan
kekerasan."
Tenba terus gelisah, tapi Takeo menikmati
tantangan untuk membujuk Tenba agar
tenang, dan ikatan di antara mereka berdua
semakin kuat. Bulan purnama di bulan ke-
enam sudah berubah, tapi tidak membawa
hujan yang diharapkan. Takeo takut kalau
mereka harus melewati jalur pegunungan
paling tinggi dalam keadaan hujan, dan lega
karena hawa panas makin menyengat. Kuda-
kuda semakin kurus; pengurus kuda
khawatfr' mereka makan pasir atau cacingan.
Lalat penghisap darah mengganggu manusia
dan hewan di malam hari. Sewaktu bulan
baru di bulan ketujuh muncul di ufuk timur,
halilintar berge-muruh dan petir berkilatan
di langit tiap malam, tapi tetap tidak turun
hujan.
Gemba menjadi sangat pendiam; sering-
kali saat terbangun di malam hari Takeo
melihat dia sedang duduk tanpa ber-gerak:
bermeditasi atau berdoa. Satu atau dua kali ia
bermimpi, atau membayangkan Makoto,
nun jauh di Terayama, melakukan hal yang
sama. Mimpi-mimpi Takeo menggambarkan
benang putus dan peti mati kosong, cermin
tanpa bayangan, manusia tanpa bayangan.
Ada yang tidak beres, Gemba pernah berkata,
dan ia merasakan itu dalam aliran darah dan
tulangnya. Rasa sakitnya yang berkurang
selama perjalanan, kini terasa lagi, lebih sakit
dari yang pernah dirasakannya. Dengan
desakan yang hanya setengah dipahaminya,
diperintahkannya agar kecepatan perjalanan
ditingkatkan: mereka bangun sebelum
matahari terbit dan berkuda di bawah cahaya
bulan.
Sebelum bulan mencapai seperempat
bagian pertama, mereka sudah tak jauh dari
Jalur Rajawali: kurang dari sehari perjalanan,
Sakai Masaki yang berjalan lebih dulu untuk
mengintai, melaporkan.
Hutan semakin lebat di sekitar jalur itu,
pohon ek serta hornbeam, dengan pohon
cedar dan pinus di lereng yang lebih tinggi.
Mereka berkemah di bawah pepohonan; air
melimpah karena ada mata air, tapi makanan
yang mereka bawa menipis. Takeo tidur
sedikit, dan terbangun dengan seruan salah
satu pengawal, "Lord Otori!"
Saat itu matahari baru akan terbit, burung-
burung baru mulai berkicau. Matanya ter-
buka, mengira masih bermimpi: ia melihat
sekilas, seperti biasa, pertama ke barisan
kuda, lalu melihat kirin.
Hewan itu berdiri di samping Tenba, leher
panjangnya membungkuk, kakinya meregang
keluar, kepalanya dekat dengan kuda-kuda,
tanda putihnya berkilau menakutkan ditimpa
cahaya keabu-abuan.
Takeo berdiri, tubuhnya terasa kaku dan
pegal. Hiroshi yang tidur tidak jauh darinya
sudah lebih dulu berdiri.
"Kirin kembali?" pekiknya.
Seruannya membangunkan yang lain, dan
seketika itu juga kirin dikerumuni.
Hewan itu menunjukkan semua tanda
gembira karena berada di antara mereka:
menggosokkan hidungnya pada Shigeko,
serta menjilati tangan Hiroshi dengan lidah
abu-abu panjangnya. Kulitnya tergores di
mana-mana, lututnya berdarah; bagian
belakang kaki kirinya tidak apa-apa, dan di
lehernya ada bekas luka gesekan tali, seolah
hewan itu berjuang melepaskan diri.
"Apa artinya ini?" tanya Takeo dengan
gempar. Dibayangkannya hewan itu lari
melintasi daerah yang tidak dikenalnya,
langkah panjangnya yang canggung,
ketakutan dalam kesendiriannya. "Bagaimana
hewan ini bisa kabur? Apakah mereka
melepasnya?"
Shigeko menjawab, "Itulah yang kutakut-
kan. Seharusnya kita tinggal lebih lama,
memastikan agar kirin senang. Ayah, biarkan
aku yang mengembalikannya."
"Sudah terlambat," sahuinya. "Lihatlah;
kita tak bisa menyerahkannya pada Kaisar
dalam kondisi-seperti ini."
"Dia takkan sanggup bertahan dalam
perjalanan," sahut Hiroshi setuju. Pemuda
itu pergi ke mata air, mengisi ember dengan
air dan membiarkan kirin minum, kemudian
mulai membasuh darah kering di badannya.
Kulitnya mengkerut dan gemetar tapi tetap
berdiri tenang. Tenba meringkik pelan
melihatnya.
"Apa artinya ini?" tanya Takeo pada
Gemba setelah hewan itu diberi makan dan
perintah dikeluarkan agar perjalanan segera
dilanjutkan. "Haruskah kita meneruskan
perjalanan dengan membawa kirin? Atau
haruskah kita mengirim semacam ganti rugi
ke Miyako?" Sejenak Takeo berhenti bicara,
menatap putrinya selagi menenangkan dan
membelai kirin. "Kaisar pasti merasa terhina
karena hewan ini kabur," lanjutnya dengan
suara pelan.
"Ya, kirin memang disambut sebagai
pertanda restu dari Surga," tutur Gemba.
"Kini hewan itu menunjukkan kalau dia
lebih memilihmu ketimbang Paduka Yang
Mulia. Pasti akan dianggap sebagai peng-
hinaan yang luar biasa."
"Apa yang harus kulakukan?"
"Bersiap untuk berperang, kurasa," sahut
Gemba tenang. "Atau mencabut nyawamu
sendiri, bila kau pikir itu lebih baik."
"Kau tahu segalanyahasil pertandingan,
penyerahan Jato, kemenanganku. Tidakkah
kau tahu yang satu ini?"
"Segala sesuatu ada sebab dan akibat,"
sahut Gemba. "Peristiwa keji seperti
kematian Taku telah melepaskan semua
rangkaian peristiwa: ini pasti salah satunya.
Mustahil bisa diramalkan atau mencegah
semuanya." Diulurkan tangannya dan me-
nepuk bahu Takeo, dengan cara yang sama
Shigeko menepuk kirin. "Maaf. Sudah
kukatakan sebelumnya bahwa ada yang tidak
beres. Aku berusaha mempertahankan
keseimbangannya, namun keseimbangannya
terputus."
Takeo menatapnya, tidak sanggup
memahami kata-katanya. "Apakah telah
terjadi sesuatu pada kedua putriku?"
Dihelanya napas dalam-dalam. "Istriku?"
"Aku tak bisa mengatakan rincian
semacam itu. Aku bukan penyihir atau
dukun. Yang kutahu hanyalah sesuatu yang
menahan jaring yang rapuh telah terputus."
Mulut Takeo terasa kering karena rasa
takut. "Bisakah diperbaiki?"
Gemba tidak menjawab, dan pada saat itu
pula, di atas hiruk pikuk persiapan, Takeo
mendengar derap langkah kuda dari
kejauhan.
"Ada yang berkuda ke arah kita," ujarnya.
Tak lama kemudian kuda-kuda dalam
barisan menaik-kan kepala dan meringkik,
dan kuda yang tengah berjalan menghampiri
meringkik balik selagi berjalan dengan santai
di sekitar kelokan jalur dan mulai kelihatan.
Ternyata itu salah satu kuda Maruyama
pemberian Shigeko kepada Lord Saga, dan
penunggangnya adalah Lord Kono.
Hiroshi berlari ke depan untuk mengambil
tali kekang sewaktu bangsawan itu meng-
hentikan kudanya; Kono melompat turun
dari punggung kudanya. Penampilannya
yang tidak bertenaga sirna sudah; laki-laki itu
kelihatan kuat dan trampil, seperti saat
pertandingan.
"Lord Otori, aku senang berhasil
menyusul Anda."
"Lord Kono," balas Takeo. "Kurasa aku
tak bisa menawarkan banyak untuk
menyegarkan diri. Kami baru saja hendak
melanjutkan perjalanan. Kami akan berada di
seberang perbatasan pada tengah hari nanti."
Takeo tidak peduli jika si bangsawan
tersinggung. Ia percaya tak ada satu hal pun
yang bisa memperbaiki posisinya sekarang
ini.
"Aku harus meminta Anda menunda
perjalanan," desak Kono. "Mari bicara
berdua saja."
"Kurasa tidak ada yang perlu dibicarakan
saat ini." Kegelisahannya telah berubah men-
jadi kemarahan. Takeo bisa merasakan
kemarahannya memuncak di balik matanya.
Selama berbulan-bulan ia telah berusaha
keras untuk bersabar dan mengendalikan
diri. Kini dilihatnya kalau semua upayanya
akan hancur oleh kejadian yang tak ber-
aturan, rasa suka kirin yang tidak terkendali
pada kawannya ketimbang dengan orang
asing.
"Lord Otori, aku tahu Anda meng-
anggapku sebagai musuh, tapi percayalah,
perhatianku pada Anda tulus dari lubuk
hatiku. Mari, beri aku waktu untuk
menyampaikan pesan Lord Saga."
Tanpa menunggu jawaban, Kono berjalan
menjauh menuju pohon cedar yang sudah
tumbang hingga seolah menyediakan tempat
duduk yang alami. Kerabat Kaisar itu duduk
dan memberi isyarat agar Takeo bergabung
dengannya. Takeo melihat sekilas ke timur.
Tepian pegunungan tampak hitam pekat ber-
lawanan dengan langit yang berkilauan, ber-
lukiskan warna keemasan.
"Kuberi waktu sampai matahari menyinari
puncak gunung," ujar Takeo.
"Ijinkan aku ceritakan apa yang terjadi.
Kemenangan dari kunjungan Anda agak
meredup dengan kepergian Anda yang lebih
awal. Tadinya Kaisar berharap bisa lebih
mengenal AndaAnda membuat Kaisar ter-
kesan. Tetap saja, Kaisar cukup gembira
dengan hadiah-hadiah pemberian Anda,
terutama hewan ini. Kaisar kemudian
khawatir melihat kirin yang kian gelisah
setelah kepergian Anda. Kaisar mengunjungi-
nya setiap hari, tapi hewan itu ketakutan,
dan tidak mau makan selama tiga hari.
Kemudian dia kabur. Kami mengejarnya,
tapi tentu saja, semua upaya kami untuk
menangkapnya gagal, dan akhirnya dia
berhasil lolos. Suasana ibukota berubah dari
gembira bahwa Kaisar direstui Surga menjadi
ejekan, bahwa restu Surga berpindah, bahwa
ternyata Lord Otori-lah yang didukung
Surga, bukannya Kaisar dan Lord Saga."
Kono berhenti sejenak. "Tentu saja, peng-
hinaan ini tak bisa diabaikan. Aku bertemu
Lord Saga saat beliau meninggalkan Sanda;
dan segera berbalik arah. Lord Saga berada
hampir tidak sampai sehari menunggang
kuda di belakangku. Kekuatan telah di-
himpun; pasukan khususnya senantiasa siaga,
dan mereka sudah siap untuk kemungkinan
semacam ini. Pasukan Anda kalah banyak
dengannya. Aku diperintahkan menyampai-
kan bahwa bila Anda tidak kembali
bersamaku dan meminta maaf pada Kaisar:
maka Anda harus bunuh diriaku khawatir
pilihan untuk mengasingkan diri sudah tidak
ada lagiSaga akan memburu Anda, dan
merebut Tiga Negara dengan paksa. Anda
dan keluarga Anda akan dihukum mati
kecuali Lady Maruyama, yang Lord Saga
harap bisa dinikahinya."
"Bukankah sejak awal dia telah meren-
canakan akan seperti ini jadinya?" sahut
Takeo, tidak berusaha mengendalikan
amarahnya. "Biarkan dia mengejarku: dia
akan kaget atas yang akan menantinya."
"Aku tidak bisa mengatakan kalau aku
terkejut, tapi menyesali keputusan Anda,"
ujar Kono. "Anda harus tahu betapa aku
mengagumi Anda...."
Takeo memotong perkataannya. "Kau
sering menyanjungku, tapi kurasa kau
berniat jahat padaku dan berusaha melemah-
kan diriku. Mungkin kau merasa dengan cara
tertentu akan dapat membalaskan dendam
atas kematian ayahmu. Jika kau memang
memiliki kehormatan atau keberanian sejati,
mestinya kau menantangku secara langsung,
ketimbang diam-diam bersekongkol dengan
Lord Arai, bawahanku dan adik iparku. Kau
ular bermuka dua yang hebat. Kau telah
menghina dan menipuku."
Wajah Kono yang sudah pucat makin
pucat. "Kita akan berjumpa dalam per-
tempuran," sahutnya. "Saat itu tipuan dan
ilmu sihir takkan bisa menyelamatkan Anda!"
Kono berdiri, dan tanpa membungkuk
hormat berjalan ke arah kudanya, melompat
ke atas punggungnya lalu menarik tali
kekang dengan kasar untuk memalingkan
kepala kudanya. Kuda itu enggan mening-
galkan kawan-kawannya, dan agak melawan,
Kono menghentakkan kaki di bagian
samping kuda itu; kuda itu bereaksi dengan
melompat dan menendang, melemparkan
bangsawan itu yang terjatuh dengan
memalukan ke tanah.
Keadaan menjadi sunyi. Dua pengawal
terdekat menarik pedang, dan Takeo tahu
semua orang berharap ia memberi perintah
untuk membunuh Kono. Ia berharap
melakukannya sendiri, sesuatu untuk
melampiaskan kemarahannya, ingin
menghukum orang yang berada di bawah
kakinya atas semua penghinaan, rencana
jahat dan pengkhianatan yang mengepung
dirinya. Tapi sesuatu mencegahnya untuk
melakukan itu.
"Hiroshi, ambil kuda Lord Kono dan
bantu dia," ujarnya, lalu berpaling agar tak
lebih mempermalukan bangsawan itu. Para
pengawal menurunkan pedang lalu menya-
rungkannya kembali.
Saat didengarnya derap langkah kaki
makin menjauh menyusuri jalan itu, Takeo
berpaling ke arah Hiroshi dan berkata,
"Kirim Sakai pergi untuk memberitahu
Kahei dan perintahkan dia bersiap untuk
berperang. Kita harus berhasil menyeberangi
jalur sempit secepat mungkin."
"Ayah, bagaimana dengan kirin?" tanya
Shigeko. "Dia kelelahan. Dia takkan sanggup
mengikuti kita."
"Hewan itu harus bisa mengikuti kita
bila tidak maka lebih baik dibunuh sekarang
juga," sahutnya, dan melihat wajah putrinya
tercengang. Besok mungkin ia akan melihat
putrinya bertarung mempertahankan diri,
Takeo sadar, namun putrinya itu belum
pernah membunuh satu makhluk hidup pun.
"Shigeko," tuturnya. "Ayah bisa menye-
lamatkanmu dan kirin hanya dengan cara
menyerahkan diri pada Lord Saga. Ayah akan
bunuh diri, kau akan menikah dengannya,
dan kita masih bisa menghindari pe-
perangan."
"Kita tidak bisa lakukan itu," sahut
Shigeko tanpa ragu. "Saga telah menipu dan
mengancam kita, serta mengingkari semua
janjinya pada kita. Akan kupastikan kirin
tidak tertinggal."
"Maka tunggangilah Tenba," sahut Takeo.
"Mereka berdua akan saling memberi
semangat."
Sebagai gantinya, Takeo mengambil kuda
Shigeko, Ashige, dan menyuruhnya berjalan
di depan bersama Gemba, seraya berpikir
kalau putrinya akan lebih aman di sana
ketimbang berada di belakang. Kemudian
muncul masalah apa yang harus dilakukan
dengan kuda beban, dan hadiah-hadiah
mewah dari Kaisar dan Lord Saga yang
mereka bawa.
Kuda-kuda itu tidak bisa mengimbangi
jalan kuda lainnyamerasa kalau Kaisar
sudah terlanjur tersinggung dan tak bisa
ditebus dengan apa pun, Takeo
memerintahkan agar bal-bal dan keranjang
ditinggalkan di dekat kuil batu kecil di tepi
mata air. Takeo menyesali kehilangan benda-
benda indah itu: jubah sutra, cermin
perunggu dan mangkuk berpernis. Ia berpikir
betapa Kaede sangat senang atas itu semua,
tapi tidak melihat ada jalan keluar lain.
Tandu pun ditinggalkannya, bahkan baju
zirah berhias indah pemberian Lord Saga.
Baju zirah itu berat dan tidak praktis, dan
Takeo lebih suka baju zirah miliknya yang
diurus oleh Kahei.
"Semua benda itu adalah sesaji untuk dewa
gunung," tuturnya pada Hiroshi, selagi
mereka berkuda menjauh. "Meski aku tidak
percaya dewa mana pun bisa menolong kita
saat ini. Apa artinya restu dari Surga? Kita
tahu kalau kirin hanyalah hewan biasa,
bukan makhluk dalam dongeng. Hewan itu
kabur karena merindukan kawannya."
"Kini kirin sudah menjadi perlambang,"
sahut Hiroshi. "Begitulah cara manusia
menghadapi dunia."
"Kini bukan saatnya untuk bicara filsafat!
Sebaiknya kita bicarakan tentang rencana
pertempuran."
"Ya, aku sudah memikirkannya sejak kita
melewati jalan ini: perbatasan di depan kita
dapat digunakan untuk bertahan meng-
hadapi pasukan Saga. Tapi apakah kini
perbatasan itu tidak dijaga? Andai aku
menjadi Saga, akan kututup semua rute yang
bisa kau lalui sebelum kau meninggalkan
ibukota."
"Itu juga terpikir olehku," aku Takeo, dan
ketakutan mereka dipastikan tak lama
kemudian saat Sakai kembali melaporkan
bahwa jalur telah dipenuhi pasukan Saga
yang bersembunyi di sela bebatuan dan
pepohonan, bersenjatakan panah dan senjata
api.
"Aku memanjat pohon dan melihat ke
belakang ke arah Timur," tutur Sakai.
"Dengan teropong aku melihat pasukan Saga
dari kejauhan, sedang mengejar kita. Mereka
mengibarkan panji-panji merah, dan pasukan
pertahanan Saga di perbatasan pasti juga
sudah melihatnya. Aku suruh Kitayama
mengitari tempat itubila orang lain bisa
melewatinya, maka dia juga bisa melewati-
nyatapi dia harus mendaki gunung dan
turun di sisi gunung yang satunya lagi
sebelum mencapai tempat Lord Miyoshi."
"Butuh berapa lama hingga dia bisa
sampai di sana?" tanya Takeo.
"Beruntung bila dia bisa sampai sebelum
malam."
"Ada berapa banyak pasukan di
perbatasan?"
"Lima puluh sampai seratus orang. Kami
tak sempat menghitungnya."
"Baiklah, pasukan kita kurang lebih
sebanding dengan jumlah pasukan musuh,"
ujar Hiroshi. "Tapi mereka memiliki semua
keuntungan dari tanah datar."
"Terlambat untuk memberi kejutan: tapi
bisakah kita mengecoh dengan mengitari
mereka?" tanya Takeo.
"Satu-satunya harapan kita adalah meng-
giring mereka ke lahan terbuka," sahut
Hiroshi. "Saat itulah kita bisa menembak
mereka satu demi satuAnda dan Lady
Shigeko harus berkuda dengan kecepatan
penuh sementara kami melindungi kalian."
Takeo terdiam merenung selama beberapa
saat, kemudian menyuruh Sakai pergi lebih
dulu bersama pengawal lainnya untuk ber-
henti tepat di depan perbatasan lalu
bersembunyi. Ia lalu menyusul Shigeko dan
Gemba.
"Ayah harus meminta kuda itu kembali,"
ujarnya. "Ayah hendak memancing musuh
keluar dari persembunyian."
"Ayah takkan pergi sendirian, kan?" tanya
Shigeko, sewaktu turun dari punggung
Tenba lalu mengambil tali kekang Ashige
dari tangan ayahnya.
"Ayah akan pergi bersama Tenba dan
kirin," sahutnya. "Tapi takkan ada yang
melihat Ayah."
Takeo jarang memperlihatkan kemampu-
an Tribe-nya pada Shigeko, atau bahkan
membicarakannya, dan kini pun ia tak ingin
menjelaskannya. Dilihatnya tatapan ragu
putrinya yang kemudian dengan cepat
dikendalikannya.
"Jangan khawatir," ujarnya. "Tak ada yang
bisa menyakiti Ayah. Tapi kau harus
menyiapkan panahmu dan bersiap untuk
menembak mati."
"Kami akan berusaha melumpuhkan
mereka ketimbang membunuh mereka,"
sahutnya seraya melirik ke arah Gemba yang
duduk diam tanpa ekspresi di punggung
kuda hitamnya.
"Ini akan menjadi pertempuran yang
sebenarnya, bukan perlombaan," tutur
Takeo, ingin putrinya siap untuk peperangan
yang haus darah. "Mungkin kelak kau tak
punya pilihan."
"Ayah harus ambil Jato kembali. Ayah
jangan pergi tanpa membawanya."
Takeo mengambil pedang itu dari
putrinya dengan rasa terima kasih. Ada
bingkai khusus yang sengaja dibuat pada
pedang itu, hingga terlalu berat bagi Shigeko
untuk membawanya; pedang itu sudah di
punggung Tenba, tepat di depan pelana.
Pedang itu masih disarungi dengan kain
upacaranya dan kelihatan luar biasa. Takeo
mengikatkan tali sutra kirin ke tali leher
Tenba dan sebelum menaiki kuda,
dipeluknya Shigeko, berdoa dalam hati bagi
keselamatan putrinya. Saat itu kira-kira
tengah hari dan cuaca sangat panas. Takeo
meraih tali kekang Tenba dengan tangan kiri,
mendongak sesaat dan melihat awan tebal
yang mengandung kilat menumpuk di arah
Barat. Tenba mengibaskan kepala menghalau
kerumunan serangga kecil yang meng-
gigitinya.
Sewaktu menunggang kuda menjauh dari
pasukan bersama kirin, Takeo menyadari ada
seseorang yang berjalan kaki mengikutinya.
Ia telah memerintahkan bahwa dia harus
pergi sendiri, lalu memalingkan pelananya
untuk memerintahkan siapa pun itu agar
kembali ke pasukan.
"Lord Otori!" Ternyata itu Mai, gadis
Muto, adik Sada.
Takeo berhenti sejenak lalu gadis itu
berjalan menghampiri ke samping kuda.
Tenba mengayunkan kepala ke arah gadis
itu.
"Mungkin aku bisa membantu," ujarnya.
"Ijinkan aku pergi bersama Anda."
"Kau bersenjata?"
Mai menarik sebilah belati dari balik
jubahnya. "Aku juga punya pisau lempar,
dan garotte. Lord Otori berencana meng-
gunakan kemampuan menghilang?"
Takeo mengangguk.
"Aku juga bisa menggunakannya. Apakah
Anda bermaksud memaksa musuh
menampakkan diri agar para pangawal bisa
menyerang mereka?"
"Mereka akan melihat seekor kuda perang
dan kirin berjalan sendiri. Kuharap
keingintahuan dan keserakahan akan meng-
giring mereka menghampirinya. Jangan
menyerang dulu sampai mereka berada di
daratan terbuka dan Sugita memerintahkan
tembakan pertama. Mereka pasti terbuai
dengan kecerobohannya sendiri. Berlindung
di sisi mana pun yang kelihatannya hanya
ada sedikit musuh, dan bunuh musuh
sebanyak-banyaknya semampumu. Makin
mereka kebingungan, makin bagus."
Mai tersenyum tipis. "Terima kasih, tuan.
Setiap nyawa yang kuhabisi akan mem-
balaskan dendam kakakku."
Kini aku yang memulai peperangan, pikir-
nya dengan perasaan sedih saat didesaknya
Tenba agar berjalan lagi, lalu membiarkan
kemampuan menghilang menyelimuti diri-
nya.
Jalanan itu makin curam dan berbatu, tapi
tepat di depan perbatasan, jalannya agak
menanjak dan melebar. Matahari masih
tinggi di langit, tapi sudah mulai tenggelam
di ufuk barat, dan bayang-bayang mulai
memanjang. Di kedua sisi jajaran
pegunungan, muncul dari hutan lebat, ter-
bentang Tiga Negara, kini berselimut awan.
Petir berkilatan di kejauhan, dan terdengar
gemuruh halilintar yang membuat Tenba
mengibaskan kepala dan gemetar; kirin
berjalan dengan tenang dan anggun seperti
biasa.
Dikejauhan Takeo mendengar desingan
layang-layang dan kepakan sayap burung,
keriat-keriut pepohonan tua, dan gemericik
air. Saat memasuki lembah, terdengar oleh-
nya suara berbisik, gemerisik pelan orang
berpindah tempat, helaan busur, dan bahkan
lebih mengancam lagi, bunyi ketukan senjata
api yang tengah diisi bubuk mesiu.
Sesaat darahnya membeku. Takeo tidak
takut mati; ia sudah sering bersentuhan
dengan kematian hingga tidak membuatnya
takut; terlebih lagi, ia sudah yakin kalau tak
seorang pun yang bisa membunuhnya sampai
putranya sanggup melakukannya, tapi kini
rasa takut yang nyaris tak disadarinya
muncul, pada peluru yang bisa membunuh
dari jauh, bijih besi yang mampu mengoyak
daging dan tulang. Bila aku harus mati,
ijinkan aku mati oleh pedang, ia berdoa saat
halilintar bergemuruh lagi, bila aku mati
akibat senjata api, maka itu hanya untuk
keadilan, karena akulah yang mengenalkan
serta mengembangkan benda itu.
Ia tak ingat pernah menggunakan
kemampuan menghilang saat menunggang
kuda, ia membiasakan diri untuk memisah-
kan ketrampilan ksatria dari kemampuan
Tribe. Dibiarkannya tali kekang kuda
menggantung dan mengangkat kakinya dari
sanggurdi agar tidak kelihatan ada
penunggangnya. Ia ingin tahu apa yang ada
dalam pikiran prajurit yang tengah me-
mandangi kuda dan kirin berjalan melewati
lembah. Apakah pemandangan itu mimpi,
atau legenda yang menjadi kenyataan? Kuda
hitam, dengan surai dan ekor berkilau sama
terangnya dengan pelana, pedang di samping
pelana; serta kirin, tinggi dan asing, dengan
leher panjang serta kulit yang bercorak aneh.
Terdengar olehnya desingan sebatang anak
panah: Tenba juga mendengarnya dan
terkejut, Takeo berusaha menjaga
keseimbangan tubuhnya selagi gerakan
mendadak itu menarik tubuhnya ke kanan
dan ke kiri. Tak ingin terjatuh seperti Kono
atau pun kehilangan kemampuan meng-
hilangnya karena kurang konsentrasi.
Dipelankan napasnya dan membiarkan
tubuhnya mengikuti gerakan kuda seakan
mereka adalah satu makhluk.
Anak panah itu berjatuhan ke tanah sejauh
beberapa langkah di depannya. Anak panah
itu tidak dibidik langsung ke arah hewan-
hewan itu, hanya sekadar menguji reaksi
alami mereka. Takeo membiarkan Tenba
bergerak dengan cepat dan ringan. Kemudian
ia menekan kedua kaki agak di samping
perut kuda itu, memaksanya maju, bersyukur
atas reaksi kuda itu seperti yang diharap-
kannya. Kirin pun mengikuti dengan patuh.
Terdengar teriakan di sebelah kanannya,
dari sebelah utara lembah. Tenba menegak-
kan telinga dan memutamya ke arah suara
tadi. Satu orang lagi menjawab teriakannya,
dari arah selatan. Langkah Tenba mulai
berderap dan kirin mulai berlari dengan
lompatan naik turun di sebelahnya.
Anggota pasukan mulai menampakkan
diri satu demi satu, bermunculan dari tempat
persembunyian mereka lalu berlarian ke
permukaan lembah. Mereka tidak bersenjata
berat sehingga mudah untuk mengepung dan
lebih leluasa: mereka berharap bisa
menyergap cepat. Sebagian besar mereka ber-
senjatakan busur panah, dan beberapa senjata
api, tapi mereka mengesampingkan senjata
ini.
Tenba mendengus, panik karena mereka
seperti sekawanan serigala, dan mempercepat
langkahnya sampai akhirnya melangkah
santai dan pelan lagi. Hal ini membuat lebih
banyak lagi pasukan bermunculan dan
berlarian lebih cepat, berusaha menghalangi
agar kedua hewan itu jangan ke ujung
lembah. Takeo merasakan tanah mulai
curam: mereka telah melewati titik tertinggi
lembah; bisa dilihatnya tanah datar di
bawahnya tempat pasukan Kahei menunggu.
Kini teriakan terdengar di mana-mana,
mereka berlomba-lomba menjadi orang
pertama yang memegang tali kekang kuda
perang itu untuk menyatakan menjadi milik-
nya. Di depan, lima atau enam orang
pasukan berkuda muncul dari celah antara
tebing yang curam. Tenba berderap, meliuk
bak kuda jantan tengah menggiring kuda
betina, menyeringai, bersiap menggigit;
langkah panjang kirin membuatnya seperti
melayang di atas tanah. Takeo mendengar
sebatang anak panah berdesing melewati
dirinya, dan melihat prajurit pertama
terjatuh, anak panah menembus dadanya. Di
belakangnya terdengar dentuman langkah
kuda selagi pasukannya Hiroshi ber-
hamburan memasuki lembah.
Desingan mengerikan anak panah me-
menuhi udara, bak kepakan sayap.
Terlambat, pasukan itu menyadari kalau itu
jebakan dan mulai berlarian kembali untuk
berlindung di antara bebatuan. Satu prajurit
segera tumbang, sebilah pisau berbentuk
bintang menancap di matanya, membuat
mereka yang berada di belakangnya cukup
lama merasa ragu untuk lari ke luncuran
anak panah selanjutnya. Baik Tenba maupun
kirin berada tepat di luar jangkauan, atau
kemahiran para pemanahnya memang luar
biasa, karena tak satu pun mengenai kedua
hewan itu.
Pasukan berkuda muncul di depannya,
pedang terhunus di tangan. Takeo meraba-
raba sanggurdi, memasukkan kakinya,
menguatkan diri lalu menarik Jato dengan
tangan kiri. Ia membiarkan dirinya terlihat di
waktu yang sama ketika mengayunkan
pedang ke kiri, menghantam prajurit
berkuda hingga jatuh dari pelana. Ia
menghempaskan berat badannya ke belakang
saat berusaha melambatkan gerakan Tenba,
lalu ia menebas tali yang mengikat kirin ke
kuda itu. Kirin berlari dengan canggung ke
depan sementara Tenba, mungkin mengingat
untuk apa dia dilahirkan, melambatkan
langkah dan berputar untuk menghadapi
prajurit berkuda lain yang kini mengepung
Takeo.
Dilupakannya usia dan cacat tangannya,
tangan kiri mengambil alih peran tangan
kanannya yang cacat. Jato melompat seperti
yang biasa dilakukannya, seolah bergerak atas
kehendaknya sendiri.
Ia menyadari Hiroshi yang datang
bergabung dengannya. Kuda tunggangan
Hiroshi yang berkulit abu-abu pucat
memerah karena darah. Lalu sekumpulan
prajurit datang mengelilinginya: Shigeko dan
Gemba dengan busur ter-sandang di
punggung dan pedang di tangan.
"Maju terus," serunya kepada mereka, dan
tersenyum dalam hati selagi mereka berjalan
melewatinya dan mulai berjalan menurun.
Shigeko aman, setidaknya untuk hari ini.
Bentrokan mereda dan sadar kalau pasukan
berkuda musuh yang terakhir tengah ber-
usaha menyelamatkan diri, dan prajurit
pejalan kaki juga kabur, mencari perlin-
dungan di sela bebatuan dan pepohonan.
"Apakah kita akan kejar mereka?" scru
Hiroshi, sambil mengatur napas, mem-
belokkan Keri.
"Jangan, biarkan mereka pergi. Saga pasti
sudah dekat di belakang. Jangan ditunda.
Kita sudah berada di Tiga Negara. Kita akan
bergabung dengan Kahei malam ini."
Tadi hanyalah pertempuran kecil, pikir
Takeo saat mengembalikan Jato ke sarung
dan akal warasnya mulai kembali. Per-
tempuran besar akan terjadi nanti.
"Kumpulkan prajurit kita yang terluka dan
tewas," perintahnya pada Hiroshi. "Jangan
tinggalkan satu orang pun." Kemudian
Takeo berteriak lantang, "Mai! Mai!"
Dilihatnya kedipan sosok dengan
kemampuan menghilang di sisi utara, lalu
mengarahkan Tenba menghampiri saat gadis
itu menampakkan diri. Takeo mengulurkan
tangan lalu mengayunkan gadis itu naik di
belakangnya. "Kau terluka?" serunya sambil
menengok ke belakang.
"Tidak," teriak Mai balik. "Aku mem-
bunuh tiga orang dan melukai dua orang."
Dapat dirasakannya debar jantung Mai
berpacu cepat menempel di punggungnya;
aroma keringat Mai mengingatkan Takeo
kalau sudah berbulan-bulan sejak ia tidur
dengan istrinya. Betapa ia sangat merindukan
Kaede: istrinya memenuhi pikirannya saat
mengamati lembah untuk melihat prajurit-
nya yang selamat dan mengumpulkan sisa-
sisanya. Lima orang tewas, sepertinya,
mungkin enam orang terluka. Takeo
bersedih bagi mereka yang tewas,
kesemuanya telah ia kenal selama bertahun-
tahun, dan bertekad memakamkan mereka
dengan penghormatan yang tinggi di
kampung halaman mereka di Tiga Negara.
Pasukan Saga yang tewas ditinggalkannya di
lembah, tidak bersusah payah menebas
kepala mereka atau mengurus yang terluka.
Saga akan berada di tempat ini esok hari, lalu
entah di hari yang sama atau keesokan
harinya mereka akan bertemu dalam per-
tempuran.
Suasana hatinya murung saat memberi
salam pada Kahei di tanah lapang di bawah.
Lega melihat Minoru tidak terluka, ia pergi
bersama jurutulis itu ke tenda Kahei, tempat
diceritakannya semua yang telah terjadi pada
sang komandan, serta membicarakan rencana
untuk keesokan harinya. Hiroshi membawa
kuda ke dalam barisan, tempat Takeo bisa
melihat putrinya bersama kirin. Wajah
putrinya pucat, dan entah bagaimana terlihat
agak kurus, hatinya terasa pedih melihat
penderitaan putrinya.
"Setidaknya kita tahu Saga tak bisa datang
lewat jalan lain," tutur Takeo. "Dia harus
melewati jalur sempit itu."
"Kita akan segera kirim pasukan untuk
mempertahankannya," sera Kahei.
"Tidak, akan kita biarkan terbuka. Kita
harap Saga mengira kita sedang kabur,
kehilangan semangat dan kebingungan. Dan
dia harus kelihatan seperti penyerang. Kita
sedang mempertahankan Tiga Negara, bukan
menentang Saga atau Kaisar. Kita tidak bisa
tinggal di sini dan menahannya dengan tidak
jelas. Kita haras mengalahkannya dengan
telak dan membawa kembali pasukan ke
wilayah Barat untuk menghadapi Zenko.
Kau sudah mendengar tentang kematian
Taku?"
"Aku sudah mendengar desas-desus, tapi
kami tidak ada kabar resmi dari Hagi."
"Tidak ada kabar dari istriku?"
"Tidak ada kabar sejak bulan ketiga, dan
dia juga tidak menyebutkan tentang berita
duka ini. Mungkin saat itu Kaede memang
belum mendengar kabar itu."
Hal itu membuat Takeo lebih tertekan
lagi, karena ia mengharapkan surat dari
istrinya, dengan berita tentang situasi Negara
Tengah dan wilayah Barat, begitu pula
dengan kabar tentang kesehatannya juga si
bayi.
"Aku belum mendapat kabar dari istriku;
kami pernah mendapat pesan dari Inuyama,
tapi tidak ada kabar dari Negara Tengah."
Kedua laki-laki itu terdiam sejenak,
memikirkan rumah mereka nun jauh di sana
dan anak-anak mereka.
"Baiklah, orang bilang kalau kabar buruk
tersebar lebih cepat ketimbang kabar baik,"
sera Kahei, membuang kekhawatirannya
dengan cara yang biasa, dengan kegiatan
fisik. "Mari kutunjukkan pasukan kita."
Kahei sudah mengatur pasukan dalam
formasi tempur: kekuatan utama di sisi barat
tanah datar, dan bagian samping di se-
panjang tepi utara terlindungi oleh barisan
bukit yang menonjol. Di sini ditempatkan-
nya para prajurit bersenjata api, begitu pula
dengan pasukan pemanah tambahan.
"Kita menghadapi cuaca buruk," ujarnya.
"Jika terlalu basah untuk menggunakan
senjata api, maka kita kehilangan
keuntungan terbesar kita."
Takeo berjalan bersamanya di bawah
cahaya rembulan untuk menginspeksi posisi,
penjaga juga membawakan obor ilalang.
Bulan putih semakin mendekati purnama,
namun awan gelap berarak tidak beraturan,
dan kilat menyala di langit barat. Gemba
duduk di bawah sebatang pohon runjung
kecil, di dekat kolam yang menyediakan air
buat mereka: matanya terpejam, jelas terpisah
dari hiruk pikuk kemah di sekitamya.
"Mungkin adikmu bisa terus menunda
turunnya hujan," ujar Takeo, berusaha
membangkitkan semangat dirinya dan juga
Kahei.
"Hujan atau tidak, kita harus bersiap
menyambut serangan mereka," sahut Kahei.
"Kau sudah bertempur satu kali hari ini. Aku
akan berjaga sementara kau dan pen-
dampingmu tidur."
Karena sudah berada di perkemahan sejak
bulan kelima, Kahei mengatur agar ia bisa
nyaman: Takeo mandi dengan air dingin,
makan sedikit, kemudian meregangkan
badan di bawah lipatan sutra tenda. la
langsung tertidur, dan memimpikan Kaede.
Mereka berada di penginapan di Tsuwano,
dan malam itu adalah malam pertunangan
Kaede dengan Shigeru. Dilihatnya Kaede saat
berusia lima belas tahun, wajahnya masih
mulus tanpa kerutan, tanpa goresan bekas
luka di leher, rambut tebalnya hitam tergerai.
Dilihatnya lentera berkelap-kelip di antara
mereka berdua saat Kaede menatap
tangannya lalu menaikkan pandangan ke
wajah. Dalam mimpinya, Kaede ditunangkan
dengan Shigeru sekaligus telah menjadi
istrinya; diserahkannya hadiah pertunangan
kepada Kaede, dan di saat yang bersamaan
meraih tubuh Kaede dan menariknya ke
arahnya.
Saat dirasakannya bentuk tubuh Kaede
yang amat disayanginya dalam pelukannya,
terdengar olehnya gemeletak api dan
menyadari kalau gerakannya yang tergesa-
gesa menghantam lentera hingga jatuh.
Ruangan itu meledak terbakar; api melahap
tubuh Shigeru, Naomi, Kenji...
Takeo terbangun, bau terbakar menyesak-
kan cuping hidungnya, hujan sudah me-
merciki tenda, kilat menghanguskan per-
kemahan, cahaya terangnya yang mengeri-
kan, halilintar memecah langit.*
Setelah Takeo memotong tali pengikat, kirin
terus berlari melintasi lembah, namun kaki-
nya tidak cocok dengan permukaan tanah
yang berbatu, dan segera saja langkahnya
melambat, berjalan terpincang-pincang.
Keributan di belakangnya membuatnya
panik, namun di depannya nampak sosok
manusia dan kuda yang tidak dikenalnya.
Sadar kalau orang dan kuda yang sayang
padanya masih di belakang, hewan itu
menunggu dengan kesabaran dan ke-
patuhannya yang biasa.
Shigeko dan Gemba menemukannya di
sana, lalu membawanya ke perkemahan.
Shigeko diam tanpa bicara saat melepas
pelana Ashige, mengencangkan tali di barisan
kuda. Gemba mengambil rumput kering dan
air.
Mereka dikelilingi prajurit dari per-
kemahan yang ingin mengetahui tentang
pertarungan tadi, tapi Gemba menghalau
mereka. Dia mengatakan bahwa Kahei harus
diberitahu lebih dulu, dan bahwa Lord Otori
ada di belakang mereka.
Shigeko melihat ayahnya berkuda me-
masuki perkemahan. Si gadis Muto, Mai, di
belakang ayahnya dan Hiroshi di samping-
nya. Sesaat ia merasa mereka berdua seperti
orang yang berbeda: berlumuran darah,
kejam, ekspresi kemarahan sisa pertempuran
masih tergambar di wajah mereka. Ekspresi
wajah Mai pun sama, membuat figurnya
kelihatan maskulin. Hiroshi yang pertama
turun dari kuda dan mengulurkan kedua
tangannya untuk mengangkat gadis itu turun
dari punggung Tenba. Setelah itu Takeo
turun dan menyapa Kahei, Hiroshi
mengambil tali kekang kedua kuda itu, tapi
kemudian berdiri sebentar untuk berbicara
dengan Mai.
Shigeko berharap ia memiliki pendengaran
tajam agar tahu apa yang sedang mereka
bicarakan, kemudian mencaci dirinya sendiri
karena merasa cemburu. Perasaan itu
menodai rasa lega karena temyata ayahnya
dan Hiroshi tidak terluka.
Tenba mencium bau kirin dan meringkik
keras. Hiroshi melihat ke arahnya dan
Shigeko melihat ekspresi laki-laki yang sangat
dikenalnya.
Aku mencintainya, pikir Shigeko. Aku
hanya akan menikah dengannya.
Hiroshi mengucapkan selamat tinggal
kepada Mai lalu membawa kedua kuda
menuju barisan kuda, mengikat kuda
miliknya, Keri, di samping Ashige, dan
Tenba di sebelah kirin.
"Mereka semua bahagia sekarang," ujar
Shigeko, saat hewan-hewan itu makan dan
minum. "Mereka punya makanan, punya
teman, dan sudah lupa peristiwa mengerikan
hari ini... Mereka tidak tahu apa yang
menanti besok."
Gemba meninggalkan mereka, mengata-
kan kalau dia perlu menghabiskan waktu
seorang diri.
"Dia pergi untuk menguatkan dirinya
dengan Ajaran Houou," ujar Shigeko. "Aku
harus melakukan hal yang sama. Tapi aku
merasa telah mengkhianati semua yang telah
diajarkan para Guru Besar." Ia memalingkan
wajah, seketika air mata terasa menusuk
kelopak matanya.
"Aku tak tahu apakah hari ini aku telah
membunuh," ujarnya pelan. "Tapi panahku
mengena banyak orang. Bidikanku tepat
kena sasaran: tak satu pun anak panah yang
meleset. Aku tidak ingin menyakiti anjing-
anjing itu, namun aku ingin menyakiti
orang-orang itu. Aku merasa gembira saat
darah mereka menyembur. Berapa banyak
dari mereka yang sudah mati sekarang?"
"Aku juga membunuh," tutur Hiroshi.
"Aku dilatih semasa kecil untuk hal ini, dan
sudah terbiasa. Namun kini, setelah kejadian
itu, aku merasakan penyesalan dan
kesedihan. Aku tidak tahu bagaimana lagi
cara untuk tetap setia pada ayahmu, kepada
Tiga Negara, atau melakukan semampuku
untuk melindungi ayahmu juga dirimu."
Setelah berhenti sejenak, Hiroshi lalu
menambahkan, "Besok pasti lebih buruk lagi.
Pertarungan kecil ini tidak ada apa-apanya
bila dibandingkan dengan pertempuran yang
akan terjadi nanti. Seharusnya kau tidak
terlibat. Aku tak bisa meninggalkan ayahmu,
tapi biar kusarankan agar Gemba membawa-
mu pergi. Kau bisa membawa kirin.
Kembalilah ke Inuyama, ke tempat bibimu."
"Aku juga tak ingin meninggalkan Ayah,"
ujar Shigeko, dan tidak kuasa menambahkan,
"Juga Lord Hiroshi." Dirasakan pipinya
merona merah lalu berkata, "Apa yang kau
bicarakan dengan gadis itu tadi?"
"Gadis Muto itu? Aku berterima kasih
padanya karena membantu kita lagi. Aku
sungguh-sungguh berterima kasih padanya
karena membawa kabar tentang kematian
Taku, juga karena telah bertempur bersama
kita hari ini."
"Oh! Tentu saja," sahut Shigeko, dan
memalingkan wajah ke arah kirin untuk
menyembunyikan rasa bingungnya. Ia ingin
dipeluk pemuda itu; takut kalau mereka akan
mati tanpa sempat menyatakan cinta.
Namun ia tak tahu bagaimana mengatakan
saat dikelilingi prajurit, pengurus kuda, dan
saat masa depan mereka kian tak menentu?
Kuda-kuda sudah selesai diurus: tidak ada
lagi alasan bagi mereka untuk berdiri di sana
lebih lama lagi.
"Mari berjalan-jalan sebentar," ajak
Shigeko. "Kita harus melihat medan perang,
lalu menemui ayahku."
Hari masih terang, jauh di ufuk barat
pancaran terakhir sinar matahari menyebar
keluar dari balik awan tebal. Langit di antara
tempat perlindungan mereka yang berwarna
abu-abu tua, berwama abu-abu pucat. Bulan
masih tinggi perlahan berwarna keperakan.
Shigeko tidak tahu bagaimana memulai
pembicaraan. Akhirnya Hiroshi bicara, "Lady
Shigeko," ujarnya. "Satu-satunya kecemasan-
ku saat ini adalah keselamatanmu." Nampak-
nya Hiroshi pun berusaha mengungkapkan
perasaannya. "Kau harus tetap hidup, demi
nasib seluruh negeri."
"Kau sudah seperti kakakku," tuturnya.
"Tidak ada orang lain yang lebih berarti
bagiku ketimbang dirimu."
"Perasaanku padamu jauh melebihi
perasaan kakak terhadap adiknya. Aku tak-
kan mengucapkannya padamu, namun
kenyataan kalau salah satu dari kita mungkin
mati besok. Kau adalah perempuan paling
sempurna yang pernah kukenal. Aku tahu
derajat dan kedudukan menempatkan dirimu
jauh di atas diriku, tapi aku tak bisa
mencintai atau menikah dengan orang lain
selain dirimu."
Shigeko tak kuasa menahan diri untuk
tersenyum. Kata-kata Hiroshi menghalau
kesedihannya, memenuhi dirinya dengan rasa
gembira serta keberanian.
"Hiroshi," ujarnya. "Mari kita menikah,
akan kubujuk orangtuaku. Saat ini aku tak
lagi merasa wajib menjadi istri Lord Saga
karena dia telah memperlakukan ayahku
dengan kejam. Seumur hidup, aku senantiasa
berusaha mematuhi orangtuaku dan ber-
tindak dengan benar. Tapi kini kulihat
ternyata, saat menghadapi kematian, ada hal
lain yang lebih penting. Kedua orangtuaku
mengutamakan cinta di atas kewajiban pada
orangtua mereka; mengapa aku tidak boleh
melakukan hal yang sama?"
"Aku tidak bisa melakukan apa yang ber-
tentangan dengan keinginan ayahmu," sahut
Hiroshi, dengan penuh perasaan. "Namun
mengetahui bahwa kau merasakan apa yang
kurasakan telah memuaskan semua
keinginanku."
Tidak semuanya, kuharap! Shigeko berani
berpikir demikian saat mereka berpisah.
Shigeko ingin segera menemui ayahnya,
namun ia menahan diri. Setelah mandi dan
makan, ia diberitahu kalau ayahnya sudah
tidur. Satu tenda terpisah didirikan
untuknya, lalu ia duduk sendirian dalam
waktu yang lama, berusaha mengatur
pikirannya dan mengobarkan kembali api
yang tenang dan kuat dari Ajaran Houou
dalam dirinya. Namun semua usahanya kalah
oleh kenangan yang melintas di benaknya
jeritan dalam pertempuran, bau darah, desing
anak panahdan wajah serta suara Hiroshi.
Shigeko tertidur sebentar dan terbangun
oleh gemuruh halilintar dan percikan air
hujan. Terdengar olehnya perkemahan
meledak dalam kesibukan di sekelilingnya,
dan melompat bangun, cepat-cepat
mengenakan pakaian berkuda yang
dikenakannya kemarin. Semuanya mulai
basah, jarinya terasa licin.
"Lady Maruyama!" seorang perempuan
berseru memanggil dari luar, dan Mai masuk
ke tenda membawa teh dan nasi dingin.
Sementara Shigeko makan dengan cepat, Mai
menghilang lagi. Saat kembali, gadis itu
membawa perisai pelindung dada kecil
terbuat dari kulit dan besi serta helm. "Ayah
Anda mengirimkan ini," ujarnya. "Anda
harus segera bersiap, juga kuda Anda, lalu
pergi menemui beliau. Mari kubantu Anda."
Shigeko merasakan bobot asing perisai
dada itu. Rambutnya tersangkut saat benda
itu diikat talinya. "Ikat rambutku," ujarnya
pada Mai; lalu diambil pedang dan
mengencangkannya di sabuknya. Mai
menaruh topi baja di kepala Shigeko lalu
mengikatkan talinya.
Hujan turun dengan deras, tapi langit
tampak kian pucat. Matahari hampir terbit.
Shigeko bergegas menuju barisan kuda,
melewati siraman hujan bak tirai baja abu-
abu. Takeo sudah mengenakan baju zirah,
Jato di sampingnya, menunggu kedatangan
Hiroshi dan pengurus kuda menyelesaikan
memakaikan pelana pada kuda.
"Shigeko," panggilnya tanpa tersenyum.
"Hiroshi memohon agar mengirimmu pergi,
tapi sebenarnya Ayah membutuhkan semua
orang yang ada. Saat ini terlalu basah untuk
menggunakan senjata api, dan Saga tahu ini.
Ayah yakin dia takkan menunggu hujan reda
untuk menyerang. Ayah membutuhkan kau
dan Gemba, karena kalian berdua adalah
pemanah yang baik."
"Aku senang," sahutnya. "Aku tak ingin
meninggalkan Ayah. Aku ingin bertempur di
samping Ayah."
"Tetaplah bersama Gemba," ujar Takeo.
"Bila kekalahan tak terhindar, dia yang akan
menyelamatkanmu."
"Aku akan mencabut nyawaku lebih
dulu," hardik Shigeko.
"Tidak, putriku, kau harus hidup. Jika kita
kalah, kau harus menikah dengan Saga, dan
mempertahankan negara dan rakyat kita
sebagai istrinya."
"Dan kalau kita menang?"
"Maka kau bisa menikah dengan orang
pilihanmu," sahut Takeo, matanya berkerut
melirik ke arah Hiroshi.
"Aku akan pegang janji Ayah," sahutnya
ringan, selagi mereka berdua naik ke
punggung kuda.
Takeo berkuda bersama Hiroshi menuju
bagian tengah tanah datar, tempat pasukan
berkuda berkumpul, dan Shigeko mengikuti
Gemba menuju sisi sebelah utara, tempat
pasukan pejalan kaki, pemanah dan pasukan
ber-senjata tombak berujung tajam dan
tombak berkapak tengah mengatur posisi.
Mereka berjumlah beberapa ribu orang,
para pemanah diatur dalam dua tingkat,
karena Kahei telah melatih seni tembakan
alternatif hingga hujan panah seperti
sambung menyambung. Andai keadaan tidak
basah, mereka pasti melakukan hal yang
sama untuk senjata api.
"Saga menduga kita hanya berkonsentrasi
pada senjata api," tutur Gemba. "Dia tak
menduga kalau kekuatan pemanah kita sama
hebatnya dengan pasukannya. Dia terkejut
saat pertandingan berburu anjing itu ber-
langsung, tapi tidak belajar dari kejadian itu.
Kini dia akan sama terkejutnya seperti saat
itu."
"Kita harus tetap di sini," tambahnya,
"bahkan saat pasukan bergerak memutar dan
maju. Ayahmu ingin agar kita membidik
dengan hari-hati dan menyerang pemimpin
mereka. Jangan sia-siakan sebatang anak
panah pun."
Mulut Shigeko terasa kering. "Lord
Gemba," panggilnya. "Bagaimana bisa terjadi
seperti ini? Bagaimana kita bisa gagal
menyelesaikan masalah dengan damai?"
"Ketika keseimbangan hilang dan
kekuatan laki-laki mendominasi, perang
tidak bisa dihindari," sahut Gemba.
"Beberapa luka telah diatasi oleh kekuatan
perempuan, tapi aku tak tahu apa itu. Sudah
takdir kita untuk berada di sini, takdir yang
mengharuskan kita membunuh atau ter-
bunuh. Kita harus merangkulnya dengan
segala kejernihan pikiran, dengan sepenuh
hati, bahwa sebenarnya kita tidak meng-
inginkan atau pun mencarinya."
Shigeko mendengarkan kata-kata ini, tapi
nyaris tak bisa mengingatnya, perhatiannya
dipusaikan pada pemandangan di depannya
saat matahari semakin terang: warna merah
dan emas baju zirah serta pelana, kuda yang
sudah tak sabar, dan panji-panji Otori,
Maruyama, Miyoshi dan klan lain dari Tiga
Negara.
Kemudian, dalam jumlah yang luar biasa
besar, bak semut yang terganggu keluar dari
sarang, gelombang pertama pasukan Saga
mengalir melewati perbatasan.*
Perang Takahara berlangsung lebih dari tiga
hari di tengah badai yang disertai kilat dan
petir. Perang berlangsung tiada henti dari
matahari terbit hingga matahari terbenam.
Malam harinya para prajurit merawat luka
dan membersihkan medan perang dari anak
panah yang berserakan. Jumlah pasukan Saga
Hideki lebih besar tiga berbanding satu
dengan pasukan Takeo, tapi jenderal Kaisar
itu dirintangi oleh sempitnya jalur menuju
dataran. dan posisi Takeo yang lebih meng-
untungkan. Selagi pasukan Saga merangsek
memasuki dataran, mereka dihujani anak
panah dari kanan; prajurit yang selamat dari
panah dihadang oleh pasukan utama Otori,
pertama dihadang pasukan berkuda yang
menggunakan pedang kemudian oleh
prajurit pejalan kaki.
Inilah perang paling brutal yang pernah
Takeo alami, perang yang berusaha ia
hindari. Pasukan Saga sangat disiplin dan
luar biasa terlatih. Mereka telah menakluk-
kan wilayah wilayah di utara; berharap
dianugerahi harta rampasan dari Tiga
Negara; berperang dengan restu Kaisar.
Sebaliknya, pasukan Takeo tidak hanya
berperang demi nyawa mereka, tapi juga
demi negara, kampung halaman, istri dan
anak-anak serta tanah mereka.
Miyoshi Kahei sudah bertempur bersama
pasukan Otori sejak perang Yaegahara saat
berusia empat belas tahun, hampir tiga puluh
tahun lalu. Klan Otori menderita kekalahan
besar, sebagian disebabkan oleh peng-
khianatan para pemimpin distrik. Kahei tak
pernah lupa masa-masa yang terjadi setelah
itu: penghinaan atas ksatria, penderitaan
rakyat di bawah penguasa Iida Sadamu. Ia
bertekad untuk tidak hidup dengan
kekalahan seperti itu lagi. Keyakinannya
bahwa Saga takkan bisa menang menguatkan
tekad pasukannya.
Sama pentingnya, persiapan Kahei dilaku-
kan dengan sangat teliti dan penuh pe-
rencanaan. Ia telah merencanakan operasi
militer ini sejak musim semi, serta mengatur
pengangkutan persediaan dan senjata dari
Inuyama. Dia sudah tak sabar selama
berbulan-bulan, ingin menghadapi ancaman
atas pemerintahan Takeo. Kini akhirnya
perang sudah dimulai, semangatnya ber-
kobar: hujan tak bisa dihindari, karena
sebenarnya dia ingin pasukannya meng-
gunakan senjata api. namun ada yang luar
biasa dengan senjata tradisional: busur panah
dan pedang, tombak runcing dan tombak
berkapak.
Panji-panji klan basah karena lembap;
tanah di bawah kaki dengan cepat berubah
menjadi lumpur. Kahei menyaksikan dari
lereng, kuda merah bata miliknya siap di
sampingnya. Minoru, si juratulis, duduk di
dekatnya bernaung di bawah payung,
berusaha keras namun sia-sia menjaga agar
tulisannya tetap kering serta mencatat semua
kejadian. Ketika serangan pertama pasukan
Saga dipukul mundur dan dihalau kembali
ke jalur perbatasan, Kahei melompat ke kuda
lalu bergabung dalam pengejaran itu,
pedangnya mencincang dan menyabet
punggung prajurit yang tengah melarikan
diri.
***
Di pagi di hari kedua, pasukan berkuda Saga
kembali melewati jalur sempit sebelum hari
terang, menyebar untuk mengecoh pasukan
pemanah ke utara dan mengitari sebelah
selatan dari pasukan utama Kahei. Takeo
tidak tidur selain menyaksikan semalaman,
mendengarkan suara pertama kegiatan dari
musuh. Didengarnya langkah kuda, meski-
pun kaki mereka dibungkus jerami, keriat-
keriut dan gemerincing pelana serta senjata.
Pemanah sebelah utara menembak membabi-
buta, dan hujan anak panah kurang efektif
dibandingkan hari sebelumnya. Semuanya
basah kuyupmakanan, senjata, dan
pakaian.
Ketika hari terang, perang sudah ber-
langsung lama, dan cahaya matahari yang
baru terbit menerangi pertunjukan yang
menyedihkan itu. Di bagian paling timur,
pasukan pemanah terjebak dalam per-
tarungan satu lawan satu dengan pasukan
Saga. Takeo tak berhasil melihat seorang pun
dengan jelas di tengah pertempuran sengit
itu, meski lencana setiap kelompok prajurit
pejalan kaki bisa terlihat samar di bawah
guyuran hujan. Segera dilihatnya kalau sisi
kanannya dalam ancaman, dan tidak
mendapat bantuan apa pun. Ia segera ber-
kuda untuk membantu mereka dengan Jato
di tangan. Tenba gemetaran penuh
semangat. Seakan tak lagi memiliki rasa
menyesal, ia bergerak memasuki kekejaman
pertempuran. Ia melihat, setengah sadar,
kalau Okuda berada tidak jauh di sebelah
kanannya. Ia menggerakkan Tenba ke
samping untuk menghindari tikaman pedang
ke arah kakinya, membelokkan kuda itu
menghadapi si penyerang lalu menunduk
menatap mata putra Okuda, Tadayoshi.
Bocah itu terjatuh dari kuda dan
kehilangan topi bajanya, serta terkepung
sewaktu berusaha membela diri dengan gagah
berani. Bocah itu mengenali Takeo dan ber-
teriak memanggil; Takeo mendengar
suaranya dengan jelas di tengah gemuruhnya
pertempuran. "Lord Otori!"
Ia tidak pernah tahu apakah itu seruan
menantang atau seruan minta tolong karena
Jato sudah turun ke tempurung kepalanya
dan membelahnya. Tadayoshi mati seketika
itu juga.
Kini Takeo mendengar jerit kemarahan
dan kesedihan, dan melihat ayah bocah itu
tengah berkuda ke arahnya, pedang di kedua
tangannya. Takeo merasa tidak tenang
dengan kematian Tadayoshi, dan tidak siap.
Saat itu Tenba tersandung, dan Takeo agak
tergelincir dari pelananya, terjatuh ke depan,
berusaha mencengkeram surai dengan tangan
kanannya yang cacat. Tersandungnya Tenba
membuat serangan Okuda agak berbelok,
tapi Takeo masih bisa merasakan akibatnya
karena ujung pedang Okuda mengenai
bagian atas lengannya sampai ke bahu. Kuda
Okuda terus berderap, memberi waktu bagi
Takeo dan Tenba memulihkan diri; ia tidak
merasa sakit dan mengira kalau ia tak terluka.
Okuda membelokkan kuda lalu kembali
menghampiri Takeo, jalannya dihalangi oleh
kerumunan prajurit. Namun Okuda tidak
mengacuhkan mereka semua, pandanganya
hanya tertuju kepada Takeo. Amukan laki-
laki itu membakar amarah lama dalam diri
Takeo, dan membiarkan kobarannya kian
membara karena perasaan itu menghangus-
kan penyesalan; Jato menanggapi dan
menemukan titik tak terlindungi di leher
Okuda. Gerakan yang cepat dan kuat laki-
laki itu justru membawa Jato menembus ke
dalam daging dan pembuluh darahnya.
***
Masih di hari kedua, Hiroshi dan pasukan-
nya mendesak pasukan Saga kembali ke jalur
sempit dalam serangan balasan; Kahei
memulai gerakan mengepung lalu menjepit
yang bisa menjebak pasukan musuh untuk
mundur. Keberadaan sepupunya, Sakai
Masaki, di belakangnya membuat Hiroshi
teringat perjalanan di tengah hujan seperti ini
bersama sepupunya itu saat berusia sepuluh
tahun. Di usia itu, perang merupakan hal
yang sangat diinginkannya, namun jalan
yang diikutinya sekarang adalah jalan
kedamaian, Ajaran Houou. Kini dirasa-
kannya semua darah yang mengalir dari
nenek moyangnya menggelegak dalam pem-
buluh darahnya. Dibuangnya jauh-jauh
semua pikiran lain dan berkonsentrasi pada
pertarungan, membunuh, menang, karena
masa depannya bergantung pada ke-
menangan. Bila kalah dalam perang ini, ia
merasa lebih baik terbunuh atau mencabut
nyawanya sendiri. Hiroshi bertarung dengan
kemarahan yang ia tidak tahu kalau ia
memilikinya, memengaruhi semangat
pasukan di sekitarnya, mendesak lawan
kembali ke jalur sempit, tempat mereka
terjebak di jalan yang menyempit.
Tak bisa kemana-mana, pasukan Saga
makin putus asa. Dalam salah satu desakan
balasan, Keri tumbang, darah menyembur
dari leher dan bahunya. Hiroshi menemukan
dirinya bertarung melawan dua prajurit tanpa
kuda. Lumpur menyulitkan dirinya untuk
menjejakkan kaki dan jatuh dengan satu
lutut, berpaling selagi pedang meng-
hampirinya dan terus menangkis dengan
pedangnya ke atas. Pedang kedua turun ke
arahnya: dilihatnya Sakai menghempaskan
badan di balik hujaman pedang itu; darah,
darahnya sendiri atau darah Sakai, mem-
butakan matanya. Bobot tubuh Sakai
menahan tubuhnya berada di dalam lumpur
saat pasukan yang bertempur menginjak-
injak melewati mereka. Sesaat Hiroshi tak
bisa percaya kalau beginilah akhirnya, lalu
rasa sakit menyelimuti dirinya, meneng-
gelamkan dirinya.
Gemba menemukannya saat malam,
sekarat karena kehilangan banyak darah
dengan luka sayatan di kepala dan kaki.
Luka-lukanya sudah ditutupi lumpur.
Gemba menghentikan aliran darah serta
membersihkannya sebisa mungkin, lalu
menggendong Hiroshi kembali ke belakang
barisan untuk bergabung dengan prajurit
yang terluka. Takeo berada di antara mereka,
bahu dan lengannya tersayat cukup dalam,
namun tidak berbahaya, sudah dibersihkan
dan dibalut dengan perban kertas.
Shigeko tidak terluka, wajahnya pucat
kelelahan.
Gemba berkata, "Aku menemukannya.
Dia sekarat. Sakai tewas tergeletak di atas
tubuhnya. Sakai pasti telah menyelamatkan
Hiroshi."
Dibaringkannya pemuda yang terluka itu
di bawah. Lentera telah dinyalakan, tapi
berasap di tengah hujan. Takeo berlutut di
samping Hiroshi, meraih tangannya dan
berseru memanggilnya. "Hiroshit Kawanku!
Jangan tinggalkan kami. Berjuanglah! Ber-
juanglah!"
Mata Hiroshi mengerjap-ngerjap. Napas-
nya terengah-engah; kulitnya basah oleh
keringat bercampur air hujan.
Shigeko berlutut di samping ayahnya.
"Dia tak mungkin sekarat! Dia tak boleh
mati!"
"Dia berhasil bertahan sampai sejauh ini,"
ujar Gemba. "Bisa kau lihat betapa kuatnya
dia."
"Jika dia bisa melewati malam ini, berarti
masih ada harapan," sahut Takeo setuju.
"Jangan putus asa."
"Betapa mengerikan semua ini," bisik
Shigeko. "Alangkah tidak termaafkan mem-
bunuh orang."
"Begitulah jalan hidup ksatria," ujar
Gemba. "Ksatria bertarung lalu mati."
Shigeko tak menjawab, namun air mata
bercucuran dengan deras dari matanya.
"Sampai berapa lama lagi Saga akan
bertahan seperti ini?" tanya Kahei pada
Takeo malam itu, sebelum mereka
menggunakan kesempatan istirahat singkat
untuk tidur. "Ini benar-benar gila. Dia
mengorbankan anak buahnya tanpa tujuan."
"Dia adalah orang dengan kebanggaan
yang tinggi," sahut Takeo. "Dia tidak pernah
kalah sehingga dia tidak akan mengakui
pemikiran semacam itu."
"Bagaimana kita bisa membujuknya? Kita
bisa saja menahan serangannya tanpa waktu
yang pastikuharap kau terkesan dengan
para prajuritmu; menurutku mereka sangat
luar biasatapi kita tak bisa menghindari
besarnya korban. Semakin cepat kita bisa
mengakhiri perang, semakin besar peluang
kita menyelamatkan yang terluka."
"Seperti Sugita yang malang," imbuhnya.
"Dan kau juga, tentunya. Demam karena
luka tak bisa dihindari dalam kondisi buruk
seperti ini, tanpa sinar matahari untuk
mengeringkan dan menyembuhkan. Kau
harus beristirahat besok; menjauhlah dari
medan perang."
"Lukanya tidak parah," sahut Takeo,
meski rasa sakit semakin terasa sepanjang hari
ini. "Beruntung aku sudah terbiasa memakai
tangan kiri. Aku takkan menjauh dari
perangtidak sebelum Saga mati atau
kembali ke ibukota!"
***
Shigeko menjaga Hiroshi semalaman,
memandikannya dengan air dingin, berusaha
menurunkan panas demamnya. Hiroshi
masih hidup hingga pagi hari, tapi tubuhnya
menggigil kencang sekali, dan Shigeko tak
menemukan satu pun benda kering yang bisa
menghangatkannya. Diseduhnya teh dan
berusaha membuat pemuda itu meminum-
nya: Shigeko tercabik antara tetap menjaga
Hiroshi atau kembali ke posisinya di samping
Gemba untuk melawan serangan Saga
selanjutnya. Tempat berlindung dari batang
kayu yang didirikan untuk mereka yang
terluka terus meneteskan air hujan; tanah di
bawah mereka becek dengan air hujan. Mai
sudah menghabiskan waktu siang dan malam
di sana, dan Shigeko memanggilnya. "Apa
yang harus kulakukan?"
Mai berjongkok di samping Hiroshi dan
meraba dahinya. "Ah, dia kedinginan,"
ujarnya. "Beginilah cara kami meng-
hangatkan orang sakit di Tribe." Mai ber-
baring dan mendempetkan tubuhnya ke
tubuh Hiroshi. "Berbaringlah di sebelah
sana," pcrintahnya, dan Shigeko melakukan-
nya, merasakan kehangatan tubuhnya
menyebar ke tubuh Hiroshi. Kedua gadis itu
mengapit pemuda itu tanpa bicara sampai
suhu tubuhnya mulai naik lagi.
"Dan begitulah kami menyembuhkan
luka," ujar Mai pelan, lalu menyingkirkan
perban Gemba, menjilat pinggiran luka yang
menganga dengan lidah lalu meludahkan air
liurnya ke luka tersebut. Shigeko mengulangi
gerakan yang sama, merasakan darah pemuda
itu.
Mai berkata, "Dia sekarat!"
"Tidak!" sahut Shigeko. "Beraninya kau
mengatakan begitu!"
"Dia perlu dirawat dengan benar. Kita tak
bisa melakukannya siang dan malam. Kau
harus bertempur, dan aku harus merawat
mereka yang lebih berpeluang hidup."
"Bagaimana cara kita menghentikan
perang ini?"
"Laki-laki memang suka bertarung," ujar
Mai. "Tapi bahkan laki-laki paling kejam
sekalipun akan kelelahan, terutama jika
mereka terluka." Mai menatap Hiroshi lalu
menatap Shigeko. "Sakiti si Saga itu, maka
dia akan kehilangan selera perangnya. Sakiti
dia separah luka yang Hiroshi derita maka
dia akan lari tunggang langgang mencari
tabib di Miyako."
Shigeko berkata, "Bagaimana cara men-
dekatinya? Dia tidak muncul di medan
perang, dia hanya mengarahkan pasukan dari
jauh."
"Aku akan menemukan caranya untuk
Anda," ujar Mai. "Kenakan pakaian
berwarna coklat seperti warna lumpur dan
siapkan busur dan anak panah yang paling
mematikan. Tidak banyak yang bisa kau
lakukan untuk Lord Hiroshi," imbuhnya saat
Shigeko ragu-ragu. "Dia sudah berada di
tangan para dewa."
Shigeko mengikuti semua petunjuk Mai,
membungkus kepala dan lehernya dengan
sehelai kain lebar lalu mencorengkan lumpur
di dahi dan pipinya agar tidak dikenali,
Diambilnya busur yang digunakannya untuk
bertempur, mengencangkan talinya dan
menemukan sepuluh anak panah baru, ujung
anak panah terbuat dari besi bermata satu,
dibului dengan bulu elang. Ditaruhnya
semua anak panah ini ke dalam tabung.
Sementara menunggu Mai kembali, Shigeko
duduk di samping Hiroshi, dan sesekali
membasuh wajahnya dan memberinya
minum karena saat ini dia terserang demam
lagi. Shigeko berusaha menenangkan pikiran
seperti yang pernah diajarkan kepadanya di
Terayama, oleh Hiroshi dan Guru Besar
lainnya.
Guruku yang terhormat, temanku sayang,
panggilnya dalam hati kepada Hiroshi.
Jangan tinggalkan aku!
Perang berlanjut dengan lebih kejam lagi,
membawa teriakan-teriakan yang membuat
gila, jeritan mereka yang terluka, dentingan
baja, derap kaki kuda, tapi ada semacam
kesunyian menyelimuti diri mereka berdua,
dan Shigeko merasakan jiwa mereka saling
bertaut.
Dia takkan meninggalkanku, pikirnya, dan
seketika itu juga pergi ke tendanya lalu
mengeluarkan busur kecil dan anak panah
dengan bulu burung houou miliknya: menje-
jalkan semua ini ke dalam jubahnya,
sementara disan-dangnya busur yang lebih
besar di bahu kiri, tabung anak panah di
bahu kanannya.
Saat kembali ke tempat Hiroshi, Mai
sudah kembali.
"Kau darimana?" tanya gadis itu. "Kukira
kau sudah kembali bertempur. Mari, ber-
gegaslah."
Shigeko bertanya dalam hati apakah perlu
memberitahukan Gemba kemana ia akan
pergi. Ketika tiba di puncak lereng dan
melihat pemandangan di medan perang,
disadarinya kalau ia takkan bisa menemukan
gurunya itu. Strategi Saga kini tampaknya
bisa mengungguli Otori dengan kekuatan
jumlah pasukan yang lebih besar. Pasukan
barunya masih segar dan telah beristirahat,
sementara pasukan Otori sudah bertempur
selama dua hari.
Berapa lama lagi mereka bisa bertahan?
tanyanya pada dirinya sendiri selagi
mengikuti Mai mengitari sisi selatan tanah
datar. Perasaannya sudah mati rasa melihat
begitu banyak orang yang tewas. Pasukan
Otori sudah membawa korban tewas dan
terluka dari pihak mereka ke garis belakang,
tapi pasukan Saga tergeletak di tempat
mereka jatuh. Kuda-kuda yang terluka
berusaha bangkit; segerombolan kecil kuda
menderap, sesekali berhenti dan terpincang-
pincang, berjalan ke barat daya, tali kekang
mereka yang putus bergelantungan terseret di
lumpur. Mengurus mereka sebentar, Shigeko
melihat kuda-kuda itu berhenti tepat di
depan kemah Otori. Mereka menundukkan
kepala dan mulai makan rumput, seolah
berada di padang rumput, terasing dan jauh
dari medan perang. Agak di belakang mereka
tampak kirin. Shigeko hampir tak memikir-
kannya selama dua hari ini: tidak ada yang
punya waktu untuk membangun kandang
baginya; hewan itu diikat dengan tali kekang
ke barisan kuda. Kirin terlihat menyedihkan
dan merana karena sendirian serta makin
kurus di bawah siraman hujan. Sanggupkah
hewan itu bertahan melewati cobaan berat ini
dan perjalanan panjang kembali ke Negara
Tengah? Rasa iba pada hewan itu meng-
hunjam hatinya, begitu kesepian dan jauh
dari rumahnya.
Kedua gadis itu berjalan melewati
belakang bebatuan dan tebing yang
mengelilingi tanah datar. Di sini suara per-
tempuran agak berkurang. Di sekeliling
mereka menjulang puncak-puncak Gugusan
Awan Tinggi, menghilang ditelan kabut yang
bergelayut bak gumpalan sutra yang belum
dipilin. Tanahnya berbatu dan licin; kerap-
kali mereka harus merangkak di bebatuan
besar. Kadang Mai berjalan di depan, mem-
beri isyarat kepada Shigeko untuk
menunggu. Shigeko meringkuk bernaung di
bawah tonjolan batu besar yang meneteskan
air hujan selama waktu yang dirasakan bak
seumur hidupnya. Ia merasa seakan telah
tewas dan sekarang sudah menjadi hantu,
berkeliaran di antara dua dunia.
Mai kembali keluar dari kabut bak hantu,
diam tanpa suara, dan memimpin untuk
berjalan terus. Akhirnya mereka tiba di batu
besar dan memanjat sisi sebelah selatan. Dua
batang pohon pinus kerdil melekat di puncak
batu itu, akar kedua pohon yang melingkar
dan berbentuk aneh membentuk semacam
kisi-kisi yang alami.
"Tetap menunduk," bisik Mai; Shigeko
menggeliat bergeser hingga ke posisi tempat
ia bisa melihat di sela-sela akar ke arah timur,
dan pintu masuk ke jalur sempit. Shigeko
menahan napas dan menyejajarkan tubuhnya
dengan bebatuan. Saga berada tepat di arah
depan mereka, bertengger di tebing yang
curam, tempat laki-laki itu mendapatkan
pandangan bak burung rajawali ke medan
perang di bawahnya. Saga duduk di bangku
kecil mewah berlapis pernis dan dinaungi
payung besar. Dia bersenjata lengkap dengan
pakaian warna hitam dan emas, topi bajanya
berhiaskan dua puncak emas, seperti gunung-
gunung di panji-panji hitam putih yang
berkibar-kibar di sampingnya. Beberapa
perwira yang sama cemerlang dan bersih
dengan dirinya walaupun hujan, berdiri
mengelilinginya, bersama dengan peniup
terompet perang dan kurir yang siap mem-
bawa pesan. Tepat di belakangnya, serang-
kaian tonjolan bebatuan yang terjatuh mem-
bentuk anak tangga alami menurun ke jalur
sempit. Shigeko melihat beberapa orang
melompat naik turun di anak tangga itu,
melaporkan perkembangan perang. Ia
bahkan bisa mendengar suara Saga,
mencermati suaranya yang penuh
kemarahan. Shigeko mengintip lagi dan
melihat laki-laki itu berdiri, berteriak dan
menggerakkan tangan dengan kipas perang
besi di tangannya. Para perwiranya mundur
selangkah dari kemarahan besar itu, dan
beberapa di antara mereka segera bergegas
menuruni anak tangga batu untuk masuk ke
kancah peperangan.
Mai bemapas di telinganya, "Sekarang,
saat dia berdiri. Kau hanya memiliki satu
kesempatan."
Shigeko menarik napas dalam-dalam dan
berpikir di sela setiap gerakannya. Akan
digunakannya pohon pinus terdekat untuk
menopang kakinya. Dia akan melangkah di
bawah batang togoknya: permukaan
bebatuan pasti licin, hingga ia harus mem-
pertahankan keseimbangan saat menarik
busur dari bahu dan anak panah dari tabung.
Gerakan ini telah diterapkannya ribuan kali
selama dua hari terakhir, dan bidikannya
belum pernah meleset.
Shigeko melihat sekali lagi dan memerhati-
kan titik kelemahan orang itu. Wajah terlihat
jelas, tatapan matanya kejam, dan terlihat
jelas kulit leher yang lebih putih.
Shigeko berdiri: busur meregang; anak
panah tepat sasaran; hujan memercik di
sekelilingnya. Saga melihat ke arahnya, ter-
duduk dengan susah payah; orang di
belakangnya memegang erat-erat dada Saga
di mana anak panah melubangi perisai
dadanya. Terdengar jerit kaget dan
terguncang, dan kini mereka membidiknya;
satu anak panah melesat melewatinya,
menghantam pohon pinus dan serpihan kayu
terkena wajahnya; satu tembakan lagi meng-
hantam batu di kakinya. Dirasakan satu
pukulan tajam, seolah tubuhnya tersandung
sebatang tongkat, tapi tidak merasa
kesakitan.
"Menunduk!" teriak Mai, namun Shigeko
tak bergerak, begitu pula Saga yang tak
berhenti memandangi dirinya. Ditariknya
busur yang lebih kecil dari jubahnya dan
menaruh sebatang anak panah di busur itu.
Bulu burung houou berkilat keemasan. Aku
akan mati, pikirnya, dan membiarkan anak
panah itu melesat ke arah tatapan laki-laki
itu.
Saat itu halilintar menyambar, dan udara
di sekitar mereka seketika penuh dengan
kepakan sayap. Anak buah Saga yang berada
di sekelilingnya menjatuhkan busur dan
menutup mata mereka; hanya Saga yang
tetap membuka mata, menatap anak panah
itu hingga menembus mata kirinya, dan
darah membutakan matanya.
***
Sepanjang pagi Kahei bertarung di bagian
sebelah selatan, tempat dia menambah
jumlah pasukan, takut kekuatan pasukan
Saga mengepung perkemahan dari sebelah
sana.
Terlepas dari kata-katanya yang penuh
keyakinan kepada Takeo di malam
sebelumnya. kini dia semakin cemas. Berapa
lama prajuritnya yang tidak tidur sanggup
dapat bertahan dari serangan yang seolah
takkan berakhir? Dia mengutuk hujan yang
menghalangi mereka menggunakan senjata
api, mengingat saat-saat terakhir perang
Yaegahara, ketika pasukan Otori, menyadari
pengkhianatan dan kekalahan yang tak bisa
dihindari, bertempur dengan putus asa
hingga nyaris tak seorang pun tersisa.
Ayahnya adalah salah satu dari sedikit
prajurit yang selamatapakah sejarah
keluarga itu akan terulang lagi, apakah ia pun
ditakdirkan kembali ke Hagi dengan
membawa berita kekalahan besar?
Ketakutannya semakin membakar tekad-
nya untuk meraih kemenangan.
***
Takeo bertarung di tengah, mengingat segala
yang pernah Guru ksatria dan Tribe ajarkan
untuk mengalahkan rasa lelah dan rasa sakit,
mengagumi tekad dan disiplin mereka yang
berada di sekelilingnya. Sewaktu pasukan
Saga berhasil dipukul mundur, ia menunduk
melihat Tenba terluka sayatan di bagian
dada, merahnya darah bercampur bulu yang
basah kuyup dengan air hujan. Sekarang ini,
ketika perang berhenti untuk sementara,
kuda itu seperti menyadari lukanya, dan
mulai gemetar ketakutan. Takeo turun,
memanggil seorang prajurit pejalan kaki
untuk membawa kuda itu ke perkemahan,
lalu bersiap untuk menghadapi serangan
berikutnya dengan berjalan kaki.
Sekelompok pasukan berkuda datang dari
jalur sempit, kuda-kuda seperti terbang
melewati jalur itu. Pedang-pedang berkilat,
menghabisi prajurit pejalan kaki yang
mundur ke rintangan yang telah mereka
dirikan saat pemanah di sebelah utara
meluncurkan anak panah. Banyak yang tepat
sasaran, tapi Takeo tak tahan memerhatikan
kalau jumlahnya jauh lebih sedikit
dibandingkan hari sebelumnya, dan per-
tempuran itu sedikit demi sedikit mengikis
kekuatannya. Seperti Kahei, keyakinannya
pun mulai berkurang. Ada berapa banyak lagi
pasukan yang dimiliki Saga? Persediaannya
seperti tidak ada habisnya, dan mereka semua
segar dan sudah beristirahat... seperti prajurit
berkuda yang kini hampir mendekatinya.
Dengan rasa terkejut dikenali pemimpin-
nya adalah Kono. Dilihatnya kuda
Maruyama, hadiahnya kini digunakan untuk
melawan dirinya, dan merasakan kemarahan
dirinya meluap. Setelah ayah orang ini nyaris
menghancurkan hidupnya; kini sang anak
berkomplot melawannya, berbohong pada-
nya, menyanjung sambil menyusun rencana
jahat untuk menjatuhkan dirinya. Dipegang-
nya Jato dengan erat, mengabaikan rasa sakit
dari luka di tangannya, lalu melompat
dengan cekatan ke samping agar si
bangsawan berhadapan dengannya di sebelah
kirinya.
Tebasan pertamanya yang cepat ke atas
mengenai kaki laki-laki itu dan hampir
membuatnya putus: Kono menjerit, mem-
belokkan kuda dan kembali; kini Takeo
berada di sebelah kanannya. Saat menunduk
di bawah tebasan pedang, dan hendak
menikam pergelangan Kono, terdengar
pedang di sebelahnya mengarah ke arah
punggung-nya. Ia berguling menjauh,
berusaha agar tidak terluka dengan
pedangnya sendiri. Saat ini kaki-kaki kuda
menginjak-injak di sekelilingnya. Takeo
beriuang keras menjejakkan kaki dalam
genangan lumpur. Pasukan pejalan kaki
miliknya sudah merangsek ke depan dengan
tombak dan tombak runcing; seekor kuda
terjatuh berdebam di sam-pingnya, ter-
sungkur dengan kepala lebih dulu, sudah
mati, terperosok ke lumpur yang dalam.
Seketika kilat menyala tepat di atas kepala,
dan hujan turun makin deras. Di sela-sela
deru hujan, Takeo mendengar suara lain,
musik pelan dan seperti hantu yang
menggema di seluruh tanah datar. Sejenak ia
tak memahami artinya. Kemudian kumpulan
massa di sekitarnya berkurang. Takeo berdiri,
menyeka air hujan dan lumpur dari matanya
dengan tangan kanan.
Kuda Maruyama tadi melewatinya, Kono
memegangi surai dengan dua tangan; kakinya
masih menyemburkan darah. Nampaknya
laki-laki itu tak memerharikan Takeo;
pandangannya terpaku pada keamanan jalur
sempit.
Mereka mundur, pikir Takeo tak percaya,
selagi suara terompet perang tenggelam
dalam teriakan kemenangan dan pasukan di
sekelilingnya mendesak ke depan mengejar
musuh yang melarikan diri.*
Para mantan gelandangan, dari desa mereka
di Maruyama, berjalan melintasi medan
perang untuk merawat kuda yang terluka
serta memakamkan yang tewas. Saat jenazah
dibaringkan berderet, Kahei, Gemba dan
Takeo berjalan menyusuri barisannya,
mengenali semua yang bisa mereka kenali,
sementara Minoru mencatat nama mereka.
Sedangkan pasukan Saga yang tewas
dimakamkan dalam satu kubur di tengah
tanah lapang. Menebas kepala tak diijinkan.
Tanahnya berbatu-batu sehingga kuburnya
pun tidak dalam. Burung gagak telah ber-
kumpul, saling memekik dari tebing yang
curam. Malam harinya, rubah berkcliaran
mencari mangsa.
Tonggak pagar pancang ditarik dan
sebagian disusun menjadi tandu untuk
mengangkut korban luka-luka kembali ke
Inuyama. Sisanya digunakan untuk membuat
barikade di sepanjang jalur sempit, dan
Sonoda Mitsura serta dua ratus pasukannya
tetap tinggal untuk menjaganya. Di malam
hari keesokan harinya, saat korban tewas
sudah dimakamkan, pertahanan sudah
ditempatkan dan tidak ada tanda-tanda Saga
kembali, sepertinya perang telah berakhir.
Kahei memerintahkan pasukan beristirahat;
mereka melepas baju zirah, meletakkan
senjata, dan segera tertidur.
Hujan deras saai Saga Hidcki memerintah-
kan pasukannya mundur, kini berubah
menjadi gerimis. Takeo berjalan di antara
pasukan yang tertidur sama seperti ketika
berjalan di antara korban tewas sebelumnya.
Ia mendengarkan desis lembut rintik air
hujan di dedaunan dan bebatuan, percik air
terjun di kejauhan, kicau burung, merasakan
butiran embun di wajah dan rambutnya.
Seluruh bagian kanan tubuhnya, dari tumit
hingga ke bahu, terasa sakit sekali, dan
kelegaan atas kemenangan tenggelam oleh
kesedihan melihat harga yang harus dibayar.
Ia tahu kalau para prajurit yang kelelahan itu
hanya bisa tidur sampai matahari terbit,
kemudian harus berjalan ke Inuyama, lalu ke
Negara Tengah untuk mencegah Zenko
membangun kekuatan di wilayah Barat. Ia
amat cemas, ingin pulang secepatnya;
peringatan Gemba tentang peristiwa yang
telah mengacaukan keselarasan pemerin-
tahannya kembali menyiksa dirinya. Itu
hanya bisa berarti sesuatu telah terjadi pada
Kaede...
Hiroshi telah dipindahkan ke dalam tenda
Kahei yang menawarkan kenyamanan
tertinggi, dan terlindung dari hujan. Takeo
menemukan putrinya di sana, masih
mengenakan baju perang, wajahnya masih
berlumuran lumpur, kakinya diperban
dengan asal-asalan.
"Bagaimana keadaannya?" tanyanya,
sambil berlutut di samping Hiroshi,
memerhatikan wajah pucat dan napasnya
yang terputus-putus.
"Dia masih hidup," sahut Shigeko dengan
suara pelan. "Kurasa dia agak membaik."
"Kita akan membawanya ke Inuyama
besok. Tabib Sonoda akan merawatnya."
Takeo bicara dengan yakin, meski
sebenarnya ia memperkirakan Hiroshi takkan
bertahan dalam perjalanan. Shigeko meng-
angguk tanpa bicara.
"Kau terluka?" tanya Takeo.
"Sebatang anak panah mengenai kakiku.
Tidak parah. Aku tak menyadarinya sampai
setelah itu. Aku hampir tak bisa berjalan
kembali. Mai yang menggendongku."
Takeo tidak mengerti ucapan putrinya.
Shigeko menatapnya dan berkata dengan
cepat, "Mai mengajakku ke tempat Lord
Saga. Aku memanah matanya." Mendadak
air mata mengambang di pelupuk matanya.
"Dia takkan mau menikahiku sekarang!" Air
matanya seketika berubah menjadi tawa.
"Jadi kami harus berterima kasih padamu
atas mundurnya pasukan Saga yang tiba-tiba
itu?" Takeo tak kuasa menahan perasaannya
atas hasil yang adil ini. Saga tidak menerima
kekalahan dalam pertandingan, dia mencari
konflik: kini Shigeko membuat dia terluka
parah, bahkan mematikan, dan telah
memastikan kemenangan mereka.
"Aku tidak bermaksud membunuhnya,
hanya melukai," ujarnya. "Seperti yang selalu
kulakukan selama perang, melumpuhkan tapi
tidak membunuh."
"Kau telah melakukan tugasmu dengan
luar biasa," sahut Takeo, "Kaulah pewaris
sejati Klan Otori dan Maruyama."
Pujian Takeo membuat air matanya
berlinang lagi.
"Kau lelah," ujar Takeo.
"Tidak lebih lelah dibandingkan yang
lainnya; tidak lebih lelah dibandingkan Ayah.
Ayah harus tidur."
"Pasti, segera setelah memeriksa keadaan
Tenba. Ayah ingin menungganginya kembali
ke Inuyama. Kahei akan membawa pasukan.
Kau dan Gemba harus mendampingi Hiroshi
dan korban luka lainnya. Semoga Tenba siap:
bila tidak siap, Ayah akan meninggalkannya
bersamamu."
"Dan kirin," ujar Shigeko.
"Ya, bersama kirin yang malang. Hewan
itu tidak tahu perjalanan panjang seperti apa
yang menantinya, atau akibat apa yang akan
terjadi di negeri ini."
"Ayah jangan berkuda seorang diri. Ajak
seseorang. Ajak Gemba. Dan Ayah boleh
menunggang Ashige; aku tidak membutuh-
kan kuda."
Awan agak menghilang, dan cahaya redup
matahari menyembul saat matahari ter-
benam, pertanda munculnya pelangi di
langit. Takeo berharap itu berarti besok akan
lebih kering, meski saat ini hujan sudah
mulai turun, dan mungkin akan berlangsung
selama berminggu-minggu.
Tenba berdiri di sebelah kirin, kembali ke
bawah rintik hujan, dengan kepala ter-
tunduk. Kuda itu meringkik pelan menyapa
saat Takeo menghampiri. Luka di dadanya
sudah tertutup dan tampak bersih, tapi kaki
kanan kuda itu agak pincang, walau kakinya
kelihatan tidak terluka. Takeo menyimpul-
kan kalau otot bahunya terkilir, membawa
kuda itu ke kolam air dan membasuhnya
dengan air dingin, tapi Tenba tetap saja lebih
menggunakan kaki kanan belakangnya, dan
kemungkinan tak bisa ditunggangi. Kemudi-
an Takeo ingat pada kuda Hiroshi, Keri. Dia
tak ada di antara kuda yang masih hidup.
Kuda abu-abu pucat bersurai hitam, anak
Raku, pasti tewas, tepat beberapa minggu
setelah kematian saudara tirinya, kuda milik
Taku, Ryume. Kuda-kuda itu mencapai usia
tujuh belas tahun, usia yang baik, tapi
kematian mereka membuat ia bersedih. Taku
telah tiada, Hiroshi di ambang kematian.
Suasana hatinya murung saat kembali ke
tenda. Di dalam tampak redup, cahayanya
memudar. Shigeko sudah tertidur di samping
Hiroshi, wajahnya dekat dengan wajah
pemuda itu. Seperti pasangan suami istri.
Takeo menatap dengan penuh kasih
sayang. "Sekarang kau boleh menikahi laki-
laki pilihanmu," ujarnya keras.
Ia berlutut di sisi Hiroshi lalu menyentuh
dahi pemuda itu. Tubuhnya dingin;
napasnya melambat dan kian dalam. Takeo
mengira Hiroshi tidak sadarkan diri, namun
Hiroshi tiba-tiba membuka mata dan
tersenyum.
"Lord Takeo...." bisiknya.
"Jangan bicara dulu. Kau akan baik-baik
saja."
"Perang?"
"Sudah berakhir. Saga mundur."
Hiroshi memejamkan mata lagi, namun
senyum masih tetap tersungging di bibirnya.
Takeo berbaring, semangatnya agak
bangkit. Meskipun lukanya terasa sakit, ia
segera tertidur, bak awan gelap yang
menghilang.
***
Ia berangkat menuju Inuyama keesokan
paginya, bersama Gembasesuai anjurkan
Shigekodan Minora. Ia berkuda di
punggung kuda betinanya yang tenang. Kuda
betina dan kuda hitam Gemba segar seperti
Ashige, dan perjalanan mereka tempuh
dengan cepat; di hari ketiga, demam ringan
menyerang Takeo. Perjalanan ditempuhnya
dalam rasa nyeri dan juga demam; ia
dihantui mimpi dan halusinasi; sesekali suhu
badannya meninggi dan gemetaran, tapi
menolak berhenti. Di setiap pemberhentian,
mereka menyebar kabar tentang perang dan
hasilnya, dan segera saja orang berduyun-
duyun ke arah Gugusan Awan Tinggi untuk
membawa makanan kepada para prajurit dan
membantu membawa korban yang terluka.
Hujan yang deras selama berhari-hari bisa
berakibat gagal panen. Jalanan berlumpur
dan acapkali tergenang air. Seringkali Takeo
lupa di mana ia berada, dan mengira tengah
berada di masa lalu, menunggangi Aoi di
samping Makoto menuju sungai yang
meluap dan jembatan yang terputus.
Kaede pasti kedinginan, pikirnya. Dia
kurang sehat. Aku harus datang dan meng-
hangatkan tubuhnya.
Namun badannya sendiri tengah gemetar,
dan sekonyong-konyong Yuki ada di
sampingnya. "Kelihatannya kau kedinginan,"
ujarnya. "Mau kuambilkan teh?"
"Ya," jawabnya. "Tapi aku tak boleh tidur
denganmu karena aku telah beristri."
Lalu diingatnya kalau Yuki sudah
meninggal, dan takkan tidur dengan dirinya
atau orang lain. Rasa menyesal menusuk
hatinya atas nasib gadis itu dan peran dirinya
dalam kematian itu.
Sewaktu tiba di Inuyama, demamnya
sudah reda dan pikirannya telah kembali
jernih, tapi hatinya tetap cemas. Kecemasan-
nya bahkan tak bisa dihilangkan dengan
sambutan sepenuh hati penduduk kota yang
merayakan kabar kemenangan dengan
menari di jalanan. Adik Kaede, Ai, keluar
menyambut di dinding sebelah luar kastil,
tempat ia dibantu turun dari kuda oleh
Minoru dan Gemba.
"Suamimu selamat," katanya dengan
segera, dan melihat wajah Ai bersinar dengan
perasaan lega.
"Syukur kupanjatkan pada Surga," sahut-
nya. "Kau terluka?"
"Kurasa aku sudah melewati bagian ter-
buruk. Apakah kau mendapat kabar dari
istriku? Aku tidak mendapat kabar apa pun
sejak kami pergi di bulan keempat."
"Lord Takeo," Ai mulai bicara, dan hati
Takeo berdebar ketakutan. Hujan turun lagi
dan para pelayan berlari ke depan membawa
payung.
"Tabib Ishida ada di sini," lanjut Ai.
"Akan kupanggil dia. Dia akan merawatmu."
"Ishida di sini? Mengapa?"
"Dia akan ceritakan semuanya," ujar Ai,
kelembutannya menakutkan Takeo. "Mari
masuk. Kau ingin mandi dulu? Dan kami
akan siapkan makanan bagi kalian."
"Ya, aku akan mandi dulu," sahutnya,
ingin bersiap dan menguatkan diri untuk
mendengar kabar itu. Demam dan nyeri
membuat kepalanya pening: pendengarannya
agak lebih peka dari biasanya, tapi begitu
jernihnya suara menyakitkan telinganya.
Ia dan Gemba berjalan ke kolam sumber
air panas dan melepas pakaian mereka yang
kotor. Dengan hati-hati Gemba menyingkir-
kan perban dari bahu dan lengan Takeo lalu
membasuh lukanya dengan air panas.
"Lukanya semakin pulih," ujar Gemba,
tapi Takeo hanya mengangguk setuju;
mereka juga tidak bicara selagi membasuh
dan mengeringkan tubuh lalu masuk ke
dalam air yang berbuih dan mengandung
belerang. Hujan membasahi lembut wajah
dan bahu mereka, mengelilingi mereka ber-
dua seakan membawa mereka ke dunia lain.
"Aku tidak bisa berlama-lama di sini,"
akhirnya Takeo berkata. "Bisakah kau ikut
denganku untuk mendengar apa yang telah
membawa Ishida ke Inuyama?"
"Tentu saja," sahut Gemba. "Mengetahui
yang terburuk adalah tahu cara bergerak
maju."
Ai sendiri yang menyajikan sop dan ikan
panggang, nasi dan sayuran musim panas.
Mereka makan dengan cepat: Ai menyuruh
pelayan membereskan nampan dan mem-
bawakan teh. Saat pelayan kembali, Ishida
datang bersama mereka.
Ai menuangkan teh ke mangkuk biru
berlapis kaca. "Akan kutinggalkan kalian."
Sewaktu Ai berlutut untuk menggeser pintu
terbuka, Takeo melihatnya mengangkat
lengan baju untuk menyeka air mata.
"Tak ada luka lainnya?" tanya Ishida,
setelah mereka saling memberi salam. "Biar
kuperiksa."
"Nanti saja," ujar Takeo. "Sudah mulai
sembuh."
Takeo menghirup teh, hampir tanpa
merasakannya. "Kau sudah jauh-jauh kemari,
kuharap kau membawa berita baik."
"Menurutku kau harus segera mendengar-
nya," sahut Ishida. "Maafkan aku, aku
merasa semua ini salahku. Kau menitipkan
istri dan putramu dalam perawatanku. Hal-
hal seperti ini memang sering terjadi; bayi
sangatlah lemah. Mereka terlepas dari geng-
gaman kita." Ishida berhenti dan menatap
tak berdaya ke arah Takeo, bibirnya berkerut
sedih, air mata berlinang di pipinya.
Darah Takeo berdentum di telinganya.
"Apakah kau hendak mengatakan kalau
putraku meninggal?" Kesedihan melanda
dirinya, dan air mata menetes. Mahkluk
mungil itu, yang nyaris belum dikenalnya,
yang kini tak akan bisa dikenalnya.
Aku tak kuasa menanggung kabar buruk
ini, pikirnya, kemudian, Bila diriku saja tak
kuasa menanggungnya, bagaimana Kaede bisa
tahan?
"Aku harus segera menemui istriku,"
ujarnya. "Bagaimana istriku menerima
keadaan ini? Apakah karena penyakit? Apa-
kah Kaede juga sakit?"
"Itu merupakan kematian di masa kanak-
kanak yang tak bisa dijelaskan," tutur Ishida,
suaranya pecah. "Bocah mungil itu sehat
pada malam sebelumnya, diberi cukup
makan, tersenyum juga tertawa, lalu tertidur
tanpa rewel, namun tidak pernah terbangun
lagi."
"Bagaimana bisa begitu?" Tanya Takeo,
nyaris marah. "Bukan karena sihir? Bagai-
mana dengan racun?" Teringat olehnya kalau
Hana berada di Hagi, mungkinkah dia
penyebab kematian putranya?
Takeo menangis, tidak berusaha menyem-
bunyikannya.
"Tak ada tanda-tanda racun," ujar Ishida.
"Sementara sihiraku benar-benar tidak
tahu. Kematian seperti ini tidak wajar, tapi
aku sama sekali tak tahu penyebabnya."
"Lalu istriku: bagaimana keadaannya? Dia
pasti hampir gila karena sedih. Apakah
Shizuka bersamanya?"
"Banyak hal buruk terjadi sejak kau pergi,"
bisik Ishida. "Istriku baru saja kehilangan
putranya. Sepertinya dia menjadi gila karena
sedih. Dia duduk tanpa makan di depan
Daifukuji, di Hofu, dan menyerukan pada
putra sulungnya untuk bertindak dengan
adil. Sebagai jawabnya, Zenko mundur
dalam keadaan gusar ke Kumamoto, tempat
dia membangun kekuatan militer."
"Istri Zenko dan putranya berada di
Hagi," ujar Takeo. "Tentu dia tidak akan
menyia-nyiakan nyawa mereka."
"Hana dan kedua putranya sudah tidak di
Hagi," ujar Ishida.
"Apa? Kaede membiarkan mereka pergi?"
"Lord Takeo," tutur Ishida dengan sedih.
"Kaede pergi bersama mereka. Mereka dalam
perjalanan ke Kumamoto."
"Ah!" ujar Gemba pelan. "Kini kita tahu
apa yang salah." Dia tak menangis, namun
ekspresi kesedihan serta welas asih terlukis di
wajahnya. Dia bergeser mendekati Takeo,
seakan ingin menopang tubuh Takeo.
Takeo duduk diam membeku. Telinganya
sudah mendengar kata-kata itu, namun
benaknya masih belum memahaminya.
Kaede meninggalkan Hagi? Dia pergi ke
Kumamoto, menyerahkan diri ke tangan
yang tengah berkomplot menentang dirinya?
Mengapa istrinya mau melakukan hal
semacam itu? Bergabung dengan suami adik-
nya? Tidak bisa dipercaya kalau istrinya
melakukan itu.
Namun sebagian dalam dirinya merasa
tercabik-cabik, seolah seluruh tangannya
terenggut habis. Dirasakan semangatnya naik
turun menuju kegelapan, dan melihat kalau
kegelapan itu akan melahap seluruh negara-
nya.
"Aku harus menemuinya," ujarnya.
"Gemba, siapkan kuda. Kira-kira sudah
sampai di mana mereka sekarang? Kapan
mereka berangkat?"
"Aku pergi kira-kira dua minggu lalu,"
sahut Ishida. "Mereka pasti pergi beberapa
hari kemudian, lewat Tsuwano dan
Yamagata."
"Bisakah aku mencegat mereka di
Yamagata?" tanya Takeo pada Gemba.
"Jaraknya seminggu berkuda."
"Aku akan sampai di sana dalam tiga hari."
"Mereka berjalan dengan lambat," tutur
Ishida. "Tak satu pun sanggup menghibur
atau mencegah kepergiannya. Yang terpikir
olehku adalah meminta bantuan Ai, maka
aku pergi diam-diam dari Hagi, seraya
berharap bertemu denganmu dalam per-
jalanan pulang."
Ishida tidak memandang Takeo: sikap
bersalah sekaligus bingung. "Lord Takeo,"
lanjutnya, tapi Takeo tak mengijinkannya
melanjutkan. Benaknya seketika mulai ber-
pacu, mencari-cari jawaban, membantah dan
memohon, menjanjikan apa saja pada dewa
manapun, agar istrinya tidak meninggalkan
dirinya.
"Hiroshi luka parah, Shigeko luka ringan,"
tutur Takeo. "Kirin juga mungkin butuh
perhatianmu. Rawat mereka sebaik-baiknya,
dan begitu sanggup bepergian, bawa mereka
ke Yamagata. Aku akan ke sana dan mencari
tahu apa yang telah terjadi. Minoru, kirim
pesan sekarang juga kepada Miyoshi Kahei;
beritahukan keberangkatanku." Takeo ber-
henti bicara lalu menatap Gemba dengan
pandangan penuh kesedihan.
"Aku harus bersiap untuk bertarung
melawan Zenko. Tapi bagaimana aku
sanggup berperang melawan istriku sendiri?"*
Di Hofu, gelombang pasang di awal bulan
kelima datang setelah siang hari di Waktu
Kuda*. Pelabuhan dalam puncak kesibukan-
nya, dengan arus kapal yang datang dan pergi
memanfaatkan angin barat untuk menuju
Akashi dengan membawa hasil bumi Tiga
Negara. Rumah makan dan penginapan
dijejali orang yang baru turun dari kapal.
Mereka minum sambil bertukar berita dan
cerita, menyuarakan kekagetan dan
penyesalan atas kematian Muto Taku;
mengagumi mukjizat yang dialami Shizuka,
yang diberi makan oleh burung-burung di
Daifukuji; kesal pada Zenko yang sangat
tidak berbakti pada orangtua dan menghina
dewa-dewa serta pasti akan dihukum atas
perbuatannya. Penduduk Hofu adalah orang-
orang yang pemberani dan juga keras kepala.
Mereka membenci perbudakan oleh Tohan
dan Noguchi; maka mereka pun tak ingin
kembali ke masa-masa di bawah kepemim-
pinan Arai. Kepergian Zenko dari kota itu
disertai dengan cemooh dan berbagai bentuk
*) Waktu Kuda: berkisar antara jam 11.00 s/d jam 13.00. [peny]
ungkapan dendam atau kebencian: para
pengawal Arai yang berada di bagian
belakang rombongan bahkan dilempari
kotoran atau sampah, bahkan dilempari batu.
Miki dan Maya melihat sedikit kejadian
ini; mereka berlari dengan menghilangkan
diri melewati jalan-jalan yang sempit, dengan
saru tujuan: menjauhkan diri dari Hisao dan
Akio. Maya sudah kelelahan karena tidak
tidur semalaman, pertemuan dengan Hisao,
percakapan dengan hantu perempuan. Ia
selalu menoleh ke belakang dengan gugup
saat mereka lari, seolah yakin Hisao akan
mengejar; pemuda itu takkan membiar-
kannya pergi. Dan Akio pasti sudah tahu
tentang si kucing. Hisao pasti dihukum,
pikirnya, tapi tak tahu apakah pikiran itu
membuatnya gembira atau sedih.
Merasakan kalau kemampuan meng-
hilangnya sirna saat ia kelelahan, Maya
melambatkan larinya untuk mengatur napas,
dan melihat Miki muncul kembali di
sebelahnya. Jalan di sini sepi; kebanyakan
orang berada di dalam rumah untuk makan
siang. Di luar toko kecil, seorang laki-laki
tengah berjongkok mengasah pisau dengan
batu asah, mengambil air dari kanal kecil.
Orang itu melonjak kaget melihat ke-
munculan mereka yang tiba-tiba hingga pisau
yang dipegangnya jatuh. Maya panik, tidak
berdaya. Tanpa berpikir panjang, diambilnya
pisau itu lalu dia tusuk tangan laki-laki itu.
"Apa yang kau lakukan?" pekik Miki.
"Kita butuh senjata, makanan dan uang,"
jawab Maya. "Dia akan berikan untuk kita."
Laki-laki itu menatap dengan tak percaya
pada darahnya sendiri. Maya berguling lalu
muncul di belakang laki-laki itu, melukainya
lagi, kali ini di leher.
"Beri kami makanan dan uang, atau kau
akan mati," ujarnya. "Adik, ambil pisau
juga."
Miki mengambil pisau kecil dari tempat-
nya tergetak di atas selembar kain yang
terhampar di tanah. Didekatinya laki-laki itu
di bagian tangan yang tidak terluka lalu
membimbingnya masuk ke dalam toko. Bola
matanya terbelalak ketakutan, ditunjukkan-
nya tempat dia menyimpan beberapa koin,
dan memaksakan kue mochi ke dalam geng-
gaman tangan Maya.
"Jangan bunuh aku," dia memohon. "Aku
membenci kejahatan Lord Arai: aku tahu dia
telah manghasut dewa-dewa menentangnya,
tapi aku tidak terlibat di dalamnya. Aku
hanyalah seorang perajin yang miskin."
"Dewa menghukum rakyat atas kejahatan
penguasanya," Maya mengoceh. Kalau si
bodoh ini mengira mereka adalah iblis atau
hantu, maka ia harus memanfaatkan sebaik-
baiknya.
"Apa-apaan tadi itu?" tanya Miki sewaktu
mereka meninggalkan toko, kini keduanya
bersenjatakan pisau yang disembunyikan di
balik pakaian.
"Akan kuceritakan nanti. Ayo kita cari
tempat untuk bersembunyi sebentar, tempat
yang ada airnya."
Mereka mengikuti kanal sampai ke jalan
yang mengarah keluar kota menuju utara.
Mereka tiba di jalan ke biara, hutan kecil
mengelilingi kolam sumber air. Di sini
mereka minum sebanyak-banyaknya, dan
menemukan tempat yang terlindung di balik
semak-semak, tempat mereka duduk dan ber-
bagi kue mochi. Burung gagak memekik di
ketinggian pohon cedar, dan jangkrik yang
berderik membosankan. Peluh bercucuran di
wajah kedua gadis itu, dan di balik pakaian
terasa lembap dan gatal.
Maya berkata, "Paman tengah menyiapkan
pasukan melawan Ayah. Kita harus ke Hagi
lalu memperingatkan Ibu. Bibi Hana sedang
dalam perjalanan ke sana. Ibu tidak boleh
percaya kepadanya."
"Tapi Maya, kau gunakan kemampuan
Tribe untuk melawan orang yang tidak
bersalah. Ayah melarang kita melakukan hal
itu."
"Dengar, Miki, kau tidak tahu apa yang
sudah kualami. Aku melihat Taku dan Sada
dibunuh di depan mataku. Aku ditawan
Kikuta Akio." Sesaat dikiranya kalau ia akan
menangis, tapi perasaan itu segera berlalu.
"Dan bocah itu, yang berseru-seru me-
manggilku, adalah Kikuta Hisao; dia adalah
cucu Kenji. Kau pasti pernah mendengar
tentang dia di Kagemura. Ibunya, Yuki,
menikah dengan Akio, tapi setelah bocah itu
lahir, Kikuta memaksanya bunuh diri. Itu
sebabnya Kenji menggiring Tribe kepada
Ayah."
Miki mengangguk, dia sudah mendengar
semua kisah Tribe ini sejak kecil.
"Lagipula, pada akhirnya, tidak ada orang
yang tidak bersalah," tutur Maya. "Sudah
menjadi takdir orang itu berada di sana saat
itu." Gadis itu menatap permukaan kolam
dengan murung. Ranting pohon cedar dan
awan di belakangnya memantul di per-
mukaan yang tenang. "Hisao adalah kakak
kita," katanya seketika. "Orang mengira dia
putra Akio, tapi sebenarnya bukan. Dia putra
Ayah."
"Itu tidak mungkin," ujar Miki dengan
suara lemah.
"Benar. Dan ada ramalan yang mengata-
kan bahwa Ayah hanya bisa dibunuh oleh
putranya sendiri. Hisao akan membunuh
Ayah, kecuali bila kita mencegahnya."
Maya menatap Miki. Dia hampir lupa
akan keberadaan bayi yang baru lahir, seolah
dengan tidak mengakui kelahiran adiknya
itu. Maya belum pernah melihatnya, mau-
pun memikirkannya. Seekor nyamuk
hinggap di tangannya dan dia menepuknya.
Miki berkata, "Ayah pasti tahu tentang
ini."
"Kalau sudah tahu, mengapa Ayah tidak
berbuat apa-apa?" sahut Maya, merasa heran
mengapa hal ini membuat ia begitu marah.
"Jika Ayah memilih untuk tidak berbuat
apa-apa, seharusnya kita juga begitu. Lagi-
pula, apa yang bisa Ayah lakukan?"
"Ayah seharusnya membunuh Hisao. Lagi-
pula Hisao pantas mendapatkannya. Dia itu
jahat, orang paling jahat yang pernah ku-
temui, lebih jahat dari Akio."
"Tapi bagaimana dengan adik bayi kita?"
tanya Miki lagi.
"Jangan membuat semuanya menjadi
rumit, Miki!" Maya berdiri mengibaskan
debu dari pakaiannya. "Aku mau pipis," ujar-
nya, menggunakan bahasa laki-laki, lalu ber-
jalan lebih jauh memasuki hutan. Di sini ada
batu nisan yang berlumut dan terbengkalai.
Maya berpikir kalau ia tak boleh mengotori-
nya, maka dipanjatnya dinding samping lalu
membuang hajat. Saat ia memanjat dengan
susah payah kembali ke sisi dinding yang
sebelumnya, bumi bergetar, dan dirasakan-
nya bebatuan merekah di bawah tangannya.
Maya setengah terjatuh ke atas tanah, merasa
pusing selama beberapa saat. Puncak pe-
pohonan cedar masih bergetar. Pada saat itu
dirasakannya keinginan untuk menjadi si
kucing, bersamaan dengan perasaan yang
tidak dikenalinya, yang membuatnya gelisah.
Ketika dilihatnya Miki duduk di samping
kolam, ia terkejut melihat betapa kurusnya
adiknya itu kini. Hal ini membuatnya merasa
kesal. Maya tak ingin mencemaskan keadaan
Miki: ia ingin segalanya tetap seperti biasa-
nya, ketika mereka seperti memiliki satu
pikiran. Ia tak ingin Miki tidak sepaham
dengan dirinya.
"Ayo," katanya. "Kita harus segera pergi."
"Apa rencana kita?" tanya Miki sewaktu
berdiri.
"Tentu saja pulang."
"Apakah kita akan berjalan kaki sampai ke
rumah?"
"Ada ide yang lebih baik?"
"Kita bisa meminta bantuan dari se-
seorang. Seorang laki-laki bernama Bunta
datang bersama Shizuka dan aku. Dia akan
menolong kita."
"Apakah dia Muto?"
"Imai."
'Tak satu pun dari mereka bisa dipercaya
lagi," sahut Maya dengan perasaan jijik.
"Kita harus pergi sendiri."
"Tapi jaraknya jauh sekali," ujar Miki.
"Butuh waktu seminggu berkuda dari
Yamagata, berkuda secara terbuka dengan
dua orang laki-laki yang membantu kita.
Dari Yamagata ke Hagi berjarak sepuluh
hari. Bila kita berjalan kaki dan sambil ber-
sembunyi, akan makan waktu tiga kali lebih
lama. Lalu bagaimana kita mendapatkan
makanan?"
"Seperti yang tadi kita lakukan," sahut
Maya, seraya menyentuh pisaunya yang
tersembunyi. "Kita akan mencurinya."
"Baiklah," ujar Miki tidak senang. "Apa-
kah kita akan mengikuti jalanan mama?" Ia
memberi isyarat ke arah jalan berdebu yang
berbelok-belok menuju sawah yang meng-
hijau ke arah pegunungan yang berselimut-
kan pepohonan. Maya mencermati para
pelancong yang berjalan menyusuri jalan itu
dari kedua arah: ksatria berkuda, perempuan
bertopi dan berkerudung lebar pelindung
sinar matahari, biarawan berjalan dengan
tongkat dan mangkuk pengemis, penjaja
dagangan, pedagang, peziarah. Be-berapa di
antara mereka mungkin saja menahan dan
menghentikan mereka berdua, yang ter-
buruk, mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang sulit. Atau mereka mungkin saja orang
Tribe yang sedang mengejar. Maya menoleh
ke belakang, ke arah kota, setengah berharap
melihat Hisao dan Akio mengejar. Ia
bimbang dan disadarinya ternyata ia rindu
dan ingin bertemu Hisao lagi.
Tapi aku membencinya! Bagaimana bisa
aku ingin berjumpa dengannya?
Berusaha menyembunyikan perasaan ini
dari Miki, ia berkata, "Walau aku berpakaian
laki-laki, siapa pun bisa melihat kalau kita
kembar. Kita tak ingin menjadi perhatian.
Kita akan berjalan melewati pegunungan."
"Kita akan kelaparan," protes Miki, "atau
tersesat. Ayo kembali ke kota saja. Ayo kita
temui Shizuka."
"Dia berada di Daifukuji," ujar Maya,
ingat perkataan gadis pelayan itu. "Berpuasa
dan berdoa. Kita boleh kembali. Akio
mungkin sudah menunggu kita di sana."
Rasa tegangnya makin bertambah; Maya
bisa merasakan tarikan itu dalam dirinya,
merasakan kalau pemuda itu sedang mencari-
nya. Mendadak Maya melompat, mendengar
suara Hisao.
Datanglah kepadaku.
Suara itu bergema seperti bisikan di sela-
sela hutan. "Kau dengar itu?" Dicengkeram-
nya tangan Miki.
"Apa?"
"Suara itu. Itu dia."
Miki berdiri, mendengarkan dengan
seksama. "Aku tidak dengar siapa-siapa,"
"Ayo pergi," ajak Maya, ia melihat ke
angkasa. Matahari sudah bergeser dari titik
puncaknya ke arah barat. Jalan hampir
mengarah ke utara, melewati sebagian besar
daerah tersubur di Tiga Negara, mengikuti
aliran sungai di sepanjang jalan menuju
Tsuwano. Sawah terbentang di kedua sisi
lembah, rumah dan gubuk petani benebaran
di tengah daerah persawahan. Jalan ter-
bentang di sepanjang sisi barat sampai ke
jembatan di Kibi. Juga ada jembatan baru,
tepat sebelum Sungai Yamagata. Sungai itu
sering meluap, tapi berjarak satu hari per-
jalanan ke utara Hofu, sungainya makin
dangkal, deburan air berbuih menghempas
bebatuan.
Mereka sudah sering melewati jalan ini;
Miki yang terakhir kali, hanya beberapa hari
lalu, sedangkan Maya saat musim gugur se-
belumnya, bersama Taku dan Sada.
"Aku penasaran di mana kedua kuda
betina itu," ujarnya pada Miki saat me-
langkah dari bawah naungan pepohonan lalu
berjalan di bawah teriknya matahari. "Kau
tahu, aku kehilangan mereka."
"Kuda betina apa?"
"Kuda pemberian Shigeko untuk per-
jalanan dari Maruyama."
Selagi mereka mulai berjalan menanjak
menaiki lereng ke pepohonan bambu, Maya
menceritakan dengan singkai tentang
serangan itu, dan kematian Taku dan Sada.
Setelah selesai bercerita, Miki menangis
tanpa suara, namun mata Maya kering.
"Aku memimpikanmu," ujar Miki, seraya
menyeka mata dengan tangan. "Aku
memimpikanmu sebagai si kucing, dan aku
adalah bayangannya. Aku tahu sesuatu yang
mengerikan terjadi padamu."
Sejenak Miki terdiam, lalu berkata, "Apa-
kah Akio menyakitimu?"
"Dia mencekikku untuk membungkam
mulutku, lalu memukulku beberapa kali,
hanya itu."
"Bagaimana dengan Hisao?"
Maya mulai berjalan lebih cepat, sampai
hampir berlari kecil di sela-sela batang pohon
yang berwarna keperakan. Seekor ular kecil
melintas di depan mereka, menghilang ke
semak belukar, dan di suatu tempat di
sebelah kiri mereka terdengar kicau burung
kecil. Derik jangkrik kedengaran makin
kencang.
Miki pun ikut berlari. Mereka menyelinap
dengan mudah di antara batang-batang
bambu.
"Hisao adalah penguasa alam baka," ujar
Maya, ketika akhirnya lereng yang semakin
curam memaksanya untuk melambatkan
langkah.
"Penguasa alam baka dari Tribe?"
"Ya. Dia bisa menjadi luar biasa kuat,
hanya saja dia tidak tahu bagaimana meng-
atasinya. Tak ada orang yang pernah meng-
ajarinya, selain cara bertindak kejam. Dan dia
bisa membuat senjata api. Kurasa ada orang
yang mengajarinya."
Matahari tergelincir di balik puncak tinggi
pegunungan di sebelah kiri mereka. Tidak
akan ada bulan, dan awan rendah menyebar
di langit dari arah selatan; juga tidak akan
ada bintang. Rasanya waktu sudah lama
berlalu sejak mereka makan kue mochi di
biara tadi. Sambil berjalan, kedua gadis itu
kini mulai secara naluriah mencari makanan:
jamur yang tumbuh di bawah pohon pinus,
wineberry, akar halus bambu, pucuk pakis
yang sudah tua, meski semua ini makin sulit
ditemukan. Sejak kecil mereka diajarkan oleh
Tribe untuk hidup dari alam, mengumpul-
kan daun, akar dan buah-buahan sebagai
makanan juga racun. Mereka mengikuti
bunyi gemericik air dan minum dari sebuah
sungai kecil. Di sungai juga menemukan
kepiting kecil yang mereka makan hidup-
hidup, mengisap daging berlumpur dari
cangkangnya yang rapuh. Kemudian mereka
melanjutkan perjalanan selama senja yang
panjang sampai malam sudah terlalu gelap
hingga tak bisa melihat apa-apa. Kini mereka
berada di lebatnya hutan, dan terdapat
banyak tebing dengan batuan yang menonjol
dan pohon tumbang yang menyediakan
tempat bernaung.
Mereka sampai di sebatang pohon beech
besar yang setengah tercabut akarnya akibat
gempa atau badai. Daun rontok selama ber-
tahun-tahun menyediakan kasur yang
empuk, dan batangnya yang besar dan akar-
nya membentuk liang. Bahkan ada kacang-
kacangan yang masih bisa dimakan di antara
dedaunan. Kedua gadis itu berbaring, be-
rangkulan. Dalam pelukan adiknya, Maya
mulai merasa rileks, seolah dirinya menjadi
utuh kembali.
Maya tidak yakin apakah dia mengucap-
kan kata-kata itu atau hanya memikirkannya.
Hisao menyayangi kucing itu dan dia
adalah penguasanya.
Miki agak memutar badannya. "Kurasa
aku tahu itu. Aku merasakannya: aku me-
mutuskan ikatan antara pemuda yang me-
manggilmu dan si kucing; dan kau berubah
ke wujud aslimu."
Tambahan lagi, ibunya selalu bersamanya.
Saat Hisao bersama si kucing, ia bisa bicara
dengan arwah ibunya."
Tubuh Miki agak gemetar. "Kau pernah
melihatnya?"
"Sudah."
Terdengar suara burung hantu di pe-
pohonan di atas mereka, membuat keduanya
melonjak kaget, dan di kejauhan terdengar
jerit rubah betina.
"Apakah saat itu kau takut?" bisik Miki.
"Tidak." Maya memikirkannya. "Tidak,"
ulangnya. "Aku merasa iba. Dia dipaksa mati
sebelum waktunya, dan harus menyaksikan
putranya diubah menjadi jahat."
"Mudah sekali menjadi jahat," ujar Miki
pelan.
Udara terasa menjadi agak dingin, dan
cahaya menerangi tanah.
"Hujan," ujar Maya. Dengan rintik-rintik
pertamanya, bau lembap mulai muncul dari
tanah. Mengisi cuping hidungnya dengan
kehidupan sekaligus kematian.
"Apa kau lari darinya? Sekalian pulang,
maksudku?"
"Dia sedang mencariku, memanggilku."
"Dia mengikuti kita?"
Maya tak langsung menjawab. Tubuhnya
menyentak-nyentak gelisah. "Aku tahu Ayah
dan Shigeko belum pulang, tapi Ibu akan
melindungi kita, kan? Begitu kita sampai di
Hagi, baru aku akan merasa aman."
Tapi bahkan setelah kata-kata itu lepas
dari mulutnya, ia pun tak yakin kalau semua
ucapannya benar. Sebagian dari dirinya takut
pada laki-laki itu dan ingin menjauh.
Sebagian lagi ditarik kembali kepadanya,
ingin bersama pemuda itu dan berjalan ber-
sama di antara dunia.
Apakah aku sudah menjadi jahat? Maya
mengingat tukang asah pisau yang dilukai
dan dirampoknya tanpa pikir panjang. Ayah
pasti marah padaku, pikirnya; merasa bersalah
dan tidak menyukai perasaan itu, ia
menuangkan rasa marah untuk memadam-
kannya. Ayah yang memaksaku; ini salah Ayah
hingga aku menjadi seperti ini. Seharusnya
Ayah tidak mengirimku pergi jauh. Seharusnya
Ayah tidak boleh begitu sering meninggalkanku
saat aku masih kecil. Seharusnya Ayah bilang
kalau Ayah punya anak laki-laki. Seharusnya
Ayah tidak boleh punya anak laki-laki!
Miki sepertinya sudah tidur. Napasnya
tenang dan teratur. Sikutnya menusuk badan
Maya, dan Maya bergeser sedikit. Suara
burung hantu tadi terdengar lagi. Nyamuk
mencium bau keringat mereka dan ber-
dengung di telinga Maya. Hujan membuat-
nya kedinginan. Nyaris tanpa berpikir dibiar-
kannya si kucing datang dengan bulu tebal-
nya yang hangat.
Segera terdengar suara Hisao. Datanglah
padaku.
Dan Maya merasakan tatapan pemuda itu
berpaling ke arahnya, seolah Hisao bisa
melihat melalui kegelapan, tepat ke mata
keemasan si kucing, saat kepalanya berputar
melihat ke arah Hisao. Kucing itu meregang-
kan badan, menegakkan telinganya serta
mendengkur.
Maya berjuang kembali ke wujud aslinya.
Dibuka mulutnya, berusaha memanggil
Miki.
Miki duduk tegak. "Apa yang terjadi?"
Maya merasakan lagi kekuatan setajam
pedang dari jiwa Miki yang menghalangi
antara si kucing dan penguasanya.
"Tadi kau melolong!" ujar Miki.
"Tadi aku berubah menjadi kucing di luar
kehendakku, dan Hisao melihatku."
"Apakah dia sudah dekat?"
"Aku tidak tahu, tapi dia tahu tempat kita
berada. Kita harus pergi sekarang juga."
Miki berlutut di pinggiran gua pohon dan
melihat dengan seksama keluar ke gelapnya
malam. "Aku tidak bisa lihat apa-apa. Gelap
gulita, dan hujan. Kita tidak bisa pergi
sekarang."
"Kau akan tetap terjaga?" tanya Maya
gemetaran karena dingin dan emosi. "Ada
sesuatu yang bisa kau lakukan yang
menghalangi antara dia dan aku, serta mem-
bebaskan diriku darinya."
"Aku tidak tahu apa itu," ujar Miki.
Suaranya lemah dan lelah. "Atau bagaimana
melakukannya. Kucing itu mengambil begitu
banyak dari dalam diriku."
Murni adalah kata yang terbersit di benak
Maya, seperti murninya baja setelah dipanas-
kan, dibengkokkan dan dipukul berulang
kali. Dipeluknya Miki dan mendekapnya
lebih erat. Berpelukan, kedua gadis itu me-
nunggu cahaya matahari merayap perlahan
menyinari mereka.
***
Hujan berhenti saat hari mulai terang, mem-
buat tanah terasa panas dan mengubah
ranting dan daun yang meneteskan air hujan
menjadi bingkai keemasan dan potongan
pelangi. Jaring laba-laba, rumpun bambu,
pakis: semuanya berkilau dan bersinar.
Dengan menjaga agar sinar matahari tetap di
kanan mereka, keduanya melanjutkan per-
jalanan ke utara, di sisi sebelah timur pe-
gunungan. Mereka berusaha sekuat tenaga
naik turun parit yang dalam, seringkali harus
menelusuri kembali jejak kaki mereka se-
belumnya; sesekali melihat jalan di bawah
sana, dan sungai di belakangnya. Meskipun
ingin berjalan sebentar di permukaan jalan
yang mulus, mereka tak berani melaku-
kannya.
Saat tengah hari, mereka berhenti di saat
yang bersamaan. Di depan mereka tampak
ada jalan yang tidak terlalu mulus, namun
menjanjikan kalau bagian selanjutnya per-
jalanan mereka akan lebih mudah. Mereka
belum makan sejak pagi, dan kini mulai
mencari-cari di rerumputan, tanpa bersuara,
dan menemukan kacang beech, lumut,
chestnut sisa musim gugur lalu yang telah
bertunas, sedikit buah beri yang hampir
ranum. Udara terasa panas, bahkan dalam
naungan lebatnya hutan.
"Kita istirahat sebentar," ujar Miki, seraya
melepas sandal dan menggosokkan telapak
kakinya di rumput yang lembap. Kakinya
lecet dan berdarah, kulitnya berubah segelap
tembaga.
Maya sudah berbaring terlentang, menatap
ke atas, ke arah hijau dedaunan yang berubah
bentuk.
"Aku lapar sekali," katanya. "Kita harus
mendapatkan makanan sungguhan. Aku
penasaran apakah jalan itu mengarah ke
sebuah desa."
Kedua gadis itu tertidur sebentar, tapi rasa
lapar membangunkan mereka. Sekali lagi,
hampir tidak perlu bicara, mereka mengen-
cangkan kembali sandal dan mulai mengikuti
jalan kecil tadi yang berkelok di sepanjang
sisi gunung. Sesekali mereka melihat atap
rumah petani jauh di bawah, dan mengira
kalau jalan kecil itu akan membawa mereka
ke sana. Tapi mereka tidak menemukan
tempat apa pun, tak ada desa, bahkan tak ada
gubuk atau biara terpencil di gunung, dan
sawah garapan tetap berada di luar jangkauan
di bawah tempat mereka berada. Mereka ber-
jalan tanpa bicara, berhenti hanya untuk
mengambil makanan yang disediakan atam,
perut mereka mulai keroncongan. Matahari
berlalu tersembunyi di balik gunung; awan
berkumpul lagi di sebelah selatan. Tak satu
pun dari kedua nya ingin menghabiskan
semalam lagi di hutan, namun tidak tahu lagi
apa yang bisa dilakukan, selain terus berjalan.
Hutan dan gunung menyatu saat senja
tiba; burung berkicau melantunkan nyanyian
pengiring matahari teng-gelam. Maya yang
berada di depan, tiba-tiba berhenti.
"Asap," bisik Miki.
Maya mengangguk, dan mereka berjalan
dengan lebih hati-hati. Baunya semakin kuat,
kini bercampur dengan aroma daging
panggang yang membuat perut mereka
semakin keroncongan. Daging burung kuau
atau kelinci, pikir Maya, karena ia pernah
mencicipi kedua daging itu di sekitar
Kagemura. Segera saja terbit air liurnya. Di
sela-sela pepohonan bisa dilihatnya sebuah
gubuk kecil. Api unggun menyala di depan-
nya, dan sesosok tubuh ramping berlutut
menjaga daging yang sedang dimasak.
Maya bisa memperkirakan dari bentuk
tubuh dan gerakannya kalau sosok itu adalah
perempuan dan ada sesuatu dengannya yang
terasa sangat familiar.
Miki berbisik di telinganya. "Perempuan
itu mirip Shizuka!"
Maya mencengkeram tangan adiknya saat
Miki hendak berlari menghampiri. "Tidak
mungkin. Bagaimana dia bisa ada di sini?
Aku akan ke sana dan melihatnya."
Menggunakan kemampuan menghilang,
Maya menyelinap di sela pepohonan dan ke
belakang gubuk. Aroma daging begitu kuat
hingga ia mengira akan kehilangan kon-
sentrasinya. Dirabanya pisaunya. Sepertinya
tidak ada orang lain lagi, hanya perempuan
itu, kepalanya tertutup tudung yang di-
pegangi dengan satu tangan sementara mem-
bolak-balik daging pada tusuk pemanggang
dengan tangan satunya lagi.
Angin sepoi-sepoi berhembus perlahan di
dataran itu dan membuat bulu-bulu coklat
dan hijau melambai-lambai terkena angin-
nya. Perempuan itu berkata, tanpa berpaling,
"Kau tak perlu menggunakan pisau itu. Aku
akan memberimu dan adikmu makan."
Suaranya mirip suara Shizuka, tapi juga
tidak mirip. Maya berpikir, Kalau dia bisa
melihatku, maka dia pasti berasal dari Tribe.
"Apakah kau Muto?" tanya Maya, lalu
membuat dirinya terlihat lagi.
"Ya, aku Muto," sahut perempuan itu.
"Kau bisa memanggilku Yusetsu."
Maya belum pernah mendengar nama itu.
Suaranya pun dingin dan misterius, bak jejak
terakhir salju yang tertinggal di sisi utara
pegunungan di musim semi.
"Apa yang kau lakukan di sini? Apakah
ayahku yang menyuruhmu ke sini?"
"Ayahmu? Takeo." Perempuan itu meng-
ucapkan nama Takeo dengan semacam
kerinduan yang dalam dan penyesalan,
lembut sekaligus getir, yang membuat Maya
bergidik. Kini perempuan itu menatap Maya,
namun tudung menutupi wajahnya. Bahkan
dengan cahaya api unggun, Maya tidak bisa
melihat wajahnya.
"Sudah hampir matang," kata Yusetsu.
"Panggil adikmu lalu cuci tangan dan kaki
kalian."
Ada teko air di anak tangga gubuk. Kedua
gadis itu bergantian menuangkan air men-
cuci tangan dan kaki mereka. Di anak
tangga, Yusetsu menaruh daging burung
kuau bakar di lembaran kulit kayu yang di-
bungkus daun. Dia lalu berlutut, mengiris
daging menjadi potongan kecil. Si kembar
makan tanpa bicara, melahap daging dengan
rakus; panasnya membakar mulut dan lidah.
Yusetsu tidak makan, dia hanya mengamati
setiap suapan mereka, memerhatikan wajah
dan tangan mereka.
Ketika keduanya sudah mengisap tulang
yang terakhir, Yusetyu menuangkan air ke
selembar kain untuk mengelap tangan
mereka. Dia membalikkan telapak tangan
mereka dan menyusuri tanda Kikuta dengan
jari-jarinya.
Kemudian ditunjuknya tempat untuk
buang hajat, dan memberikan lumut untuk
membersihkannya; sikapnya penuh perhati-
an, seolah dia adalah ibu mereka. Setelah itu
dinyalakannya lentera dari sisa api yang
masih menyala, dan mereka berbaring di
lantai gubuk sementara perempuan itu terus
memandangi mereka.
"Jadi kalian anaknya Takeo," ujarnya lirih.
"Kalian mirip dengannya. Kalian seharusnya
menjadi anakku."
Dan kedua gadis itu, dalam keadaan
hangat dan kenyang, merasakan juga lebih
baik kalau mereka memang menjadi anak
Yusetsu, meski mereka belum tahu siapa
perempuan itu sebenarnya.
Yusetsu memadamkan lentera dan menye-
limuti mereka dengan jubahnya. "Tidurlah,"
ujarnya. "Tidak ada yang bisa menyakiti
kalian saat aku di sini."
Mereka tidur tanpa bermimpi dan ter-
bangun saat hari mulai terang. Hujan
menyirami wajah mereka, juga tanah lembap
di bawah tubuh mereka. Tak ada tanda-tanda
gubuk, teko, maupun perempuan itu. Hanya
bulu burung di lumpur dan bekas bara api
yang menandakan kalau perempuan itu
pernah ada di sana.
Miki berkata, "Dia adalah hantu
perempuan itu."
"Mmm," gumam Maya, setuju.
"Ibu Hisao? Yuki?"
"Siapa lagi?" Maya mulai berjalan ke arah
utara. Tak satu pun dari keduanya bicara lagi
tentang perempuan itu, namun rasa daging
burung kuau masih tertinggal di lidah dan
tenggorokan mereka.
"Ada jalan kecil," ujar Miki, mengejar
Maya. "Seperti kemarin."
Jalannya tidak rata, seperti jalanan rubah,
melalui semak belukar. Mereka berjalan
menyusurinya sepanjang hari, beristirahat
dalam panasnya siang hari di rimbunnya
semak hazelnut. Dan berjalan lagi sampai
malam tiba saat bulan baru muncul, bulan
sabit.
Tiba-tiba tercium bau asap yang sama,
aroma daging yang tengah dimasak yang
menerbitkan air liur, seoerang perempuan
sedang menjaga makanan yang dimasak,
wajahnya tersembunyi oleh jubah bertudung.
Di belakangnya ada gubuk, teko berisi air.
"Kita di rumah," ujar Maya menyapa
dengan akrab.
"Selamat datang di rumah," sahut
perempuan itu. "Cuci tangan; makanannya
sudah matang."
"Apakah itu makanan hantu?" tanya Miki
saat perempuan itu membawakan daging
saat ini daging kelincidan mengirisnya
untuk mereka.
Yusetsu tertawa. "Semua makanan adalah
makanan hantu. Semua makanan sudah mati
dan memberikan rohnya pada kalian agar
kalian bisa hidup."
"Jangan takut," tambahnya ketika Miki
ragu; Maya sudah menjejalkan daging ke
mulutnya. "Aku di sini untuk membantu
kalian."
"Apa yang kau inginkan sebagai imbalan?"
tanya Miki, tetap belum mau makan.
"Aku membalas pertolonganmu. Aku ber-
utang padamu. Karena kau memutuskan
ikatanku dengan anakku."
"Benarkah?"
"Kau membebaskan si kucing, dan
sekaligus membebaskanku."
"Bila sudah bebas, seharusnya kau me-
lanjutkan perjalananmu," tutur Miki dengan
suara tenang dan tegas yang belum pernah
Maya dengar. "Tugasmu sudah berakhir di
dunia ini. Kau harus merelakannya, dan
membiarkan arwahmu berjalan terus menuju
kelahirannya kembali."
"Kau bijaksana," sahut Yuki. "Akan lebih
bijaksana dan lebih kuat lagi begitu kau
dewasa. Dalam waktu satu atau dua bulan
lagi, kau dan kakakmu akan mulai mendapat
haid. Menjadi perempuan membuat kalian
lemah, jatuh cinta menghancurkan diri
kalian, dan membuat seorang anak menem-
pelkan pisau di lehermu. Jangan tidur
dengan laki-laki; bila kalian tidak me-
mulainya, maka kalian takkan merindu-
kannya. Aku sangat suka bercinta; ketika aku
menganggap ayah kalian sebagai kekasihku,
aku merasa seperti di Surga. Aku mem-
biarkannya memiliki diriku seutuhnya. Aku
merindukannya siang dan malam. Dan aku
melakukan apa yang diperintahkan padaku:
kalian anak-anak Tribe; kalian harus tahu
tentang kepatuhan."
Kedua gadis itu meng-angguk, tapi tidak
bicara.
"Aku patuh pada Ketua Kikuta dan Akio,
yang kutahu mesti kunikahi di kemudian
hari. Tapi aku mengira akan menikah dengan
Takeo dan melahirkan anak-anaknya. Kami
sangat serasi dalam kemampuan Tribe, dan
kukira dia jatuh cinta padaku. Dia kelihatan
terobsesi padaku sama seperti aku terobsesi
padanya. Kemudian aku tahu kalau
Shirakawa Kaede yang dicintainya, kegilaan
karena cinta yang bodoh membawa dirinya
kabur dari Tribe dan membuat aku dihukum
mati."
Yuki terdiam membisu. Kedua gadis itu
juga tidak berkata apa-apa. Mereka belum
pernah mendengar versi cerita ini dari
riwayat orangtua mereka, diceritakan oleh
perempuan yang sangat menderita disebab-
kan oleh cintanya pada ayah mereka.
Akhirnya Maya berkata, "Hisao berusaha
untuk tidak ingin mendengarkanmu."
Miki mencondongkan badan ke depan
dan mengambil sepotong daging, mengu-
nyahnya pelan, merasakan lemak dan
darahnya.
"Dia tak mau tahu siapa dirinya," sahut
Yuki. "Sifat dalam dirinya tercabik, itu
sebabnya dia merasa sakit kepala yang sangat
menusuk."
"Dia tidak bisa dibebaskan dari dosa," ujar
Maya, amarahnya kembali lagi. "Semakin
lama dia menjadi semakin jahat."
"Kalian adalah adiknya," tutur Yuki.
"Salah satu dari kalian menjadi si kucing,
yang disayanginya; sedang yang satunya lagi
memiliki kualitas spritual yang menolak ke-
kuatannya. Bila dia menyadari kekuatan itu
sepenuhnya, maka dia akan menjadi benar-
benar jahat. Tapi sampai tiba waktunya
nanti, dia masih bisa diselamatkan." Yuki
mencondongkan badan, dan membiarkan
tudung terlepas. "Begitu dia sudah selamat,
aku akan melanjutkan perjalananku. Aku
tidak bisa membiarkan anakku membunuh
ayahnya. Namun ayah angkatnya harus
membayar pembunuhan keji atas diriku."
Dia cantik, pikir Maya, tidak seperti Ibu
tapi dengan sifat yang selalu kuingin diriku
menjadi seperti itu, kuat dan ptnuh semangat.
Aku berharap dia yang menjadi ibuku. Aku
berharap dia belum mati.
"Sekarang kalian harus tidur. Teruslah
berjalan ke utara. Aku akan memberi kalian
makan dan membimbing kalian kembali ke
Hagi. Kita akan menemukan ayah kalian dan
memperingatkannya, saat kita sudah bebas,
kita akan selamatkan Hisao."
Yuki mencuci tangan mereka seperti yang
dilakukannya di malam sebelumnya, tapi kali
ini dibelainya tangan mereka dengan lebih
lembut, layaknya seorang ibu; sentuhannya
kuat dan nyata: dia tidak terasa seperti arwah,
tapi keesokan paginya, si kembar terbangun
di hutan yang kosong. Hantu perempuan itu
sudah pergi.
Miki bahkan lebih pendiam lagi ketim-
bang sebelumnya. Suasana hati Maya labil,
bergerak antara gembira karena kemung-
kinan bertemu Yuki lagi malam itu, serta
ketakutan akan Akio dan Hisao yang sudah
dekat di balakang mereka. Dia mencoba
memaksa Miki bicara, tapi jawaban Miki
singkat dan tidak memuaskan.
"Apakah menurutmu kita melakukan hal
yang salah?" tanya Maya.
"Sekarang sudah terlambat," bentak Miki,
dan kemudian sikapnya melunak. "Kita
sudah makan makanan darinya dan me-
nerima bantuannya. Kita tidak bisa melaku-
kan apa-apa lagi; kita hanya harus segera
sampai di rumah dan berharap Ayah cepat
kembali."
"Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak
tentang hal itu?" tanya Maya, kesal dengan
kemarahan Miki. "Kau bukan seorang
penguasa alam baka juga, kan?"
"Bukan, tentu saja bukan," pekik Miki.
"Aku bahkan tidak tahu apa itu. Aku belum
pernah mendengarnya sampai kau mengata-
kan kalau Hisao adalah penguasa alam baka."
Mereka berjalan menuruni lereng yang
curam. Jalur itu berkelok di antara tonjolan
batu-batu besar: sepertinya itu tempat
kesukaan ular untuk berjemur. Sewaktu
tubuh-tubuh yang bengkok bergerak cepat
menghilang di balik bebatuan, Maya pun
bergidik. Memikirkan arwah Akane, dan
bagaimana ia menggoda Sunaomi dengan
menyaru sebagai perempuan pelacur yang
sudah mati itu.
"Menurutmu apa yang sebenarnya Yuki
inginkan?" tanyanya.
"Semua hantu ingin balas dendam," jawab
Miki. "Dia ingin balas dendam."
"Pada Akio?"
"Pada semua orang yang telah menyakiti
dirinya."
"Benar kan, kau memang tahu semuanya,"
ujar Maya.
"Mengapa dia membimbing kita ke Hagi?"
tanya Miki.
"Untuk mencari Ayah; dia yang bilang
begitu."
"Tapi Ayah belum akan kembali sampai
musim panas berakhir," lanjut Miki, seolah
membuat bantahan kepada dirinya sendiri.
***
Maka perjalanan mereka berlanjut saat bulan
semakin penuh dan menyusut lagi. Bulan
keenam tiba dan musim panas bergerak
menuju puncaknya. Yuki menemui mereka
setiap malam; mereka mulai terbiasa dengan
kehadirannya, dan tanpa disadari mulai
menyayanginya seakan perempuan itu adalah
ibu mereka. Yuki menemani mereka dari
antara matahari terbenam sampai matahari
terbit, tapi perjalanan setiap harinya terasa
lebih mudah karena kini mereka tahu Yuki
menanti mereka di penghujung hari.
Keinginannya pun menjadi keinginan
mereka berdua. Setiap malam Yuki men-
ceritakan masa lalunya: tentang masa kecil-
nya di Tribe; kesedihan terbesar pertama
dalam hidupnya, ketika temannya dari
Yamagata dibakar sampai mati bersama
semua keluarganya di malam Otori Takeshi
dibunuh prajurit Tohan; bagaimana dia
membawa pedang Lord Shigeru, Jato, lalu
menyerahkannya ke tangan Takeo setelah
sebelumnya mereka menyelamatkan Shigeru
dari kastil Inuyama; dan bagaimana Yuki
membawa kepala Lord Shigeru ke Terayama,
seorang diri, melewati negeri yang tidak
ramah. Mereka berdua kagum pada
keberanian dan kesetiaan Yuki, dan terkejut
serta gusar dengan kematiannya yang kejam,
terharu dengan kesedihan dan rasa ibanya
atas putranya.*
Si kembar tiba di Hagi di sore hari. Matahari
masih di langit barat, membuat air laut
tampak seperti kuningan. Mereka meringkuk
di hutan bambu tepat di tepi sawah, padi
berwarna hijau terang. Ladang sayuran lebat
dengan dedaunan, kedelai, wortel dan
bawang.
"Kita tidak membutuhkan Yuki malam
ini," ujar Miki. "Kita bisa tidur di rumah."
Namun pikiran itu membuat Maya sedih.
Ia akan merindukan Yuki, dan seketika
timbul niat ingin pergi ke mana pun
perempuan itu pergi.
Gelombang sedang surut dan tepi yang
berlumpur terlihat jelas di sepanjang sungai
kembar. Maya bisa melihat lengkungan
jembatan batu, dan biara bagi dewa sungai
tempat ia membunuh kucing milik Mori
Hiroki. Tiang pancang kayu dari pagar
penangkap ikan, dan perahu-perahu yang
tertambat di tepinya, bak mayat yang tengah
menanti air untuk menghidupkannya
kembali. Di belakangnya tampak pepohonan
dan taman rumah tua keluarga. Lebih jauh
ke barat, di atas atap dan sirap rendah
bangunan kota, menjulang kastil dengan
panji-panji Otori berkibar tertiup angin.
Maya memicingkan mata melihat mata-
hari. Bisa dilihatnya umbul-umbul bangau
Otori, tapi di sebelahnya ada umbul-umbul
lain, tapak beruang hitam dengan latar
belakang merah: lambang Klan Arai.
"Bibi Hana ada di sini," bisiknya pada
Miki. "Aku tidak ingin dia melihatku."
"Bibi pasti di kastil," ujar Miki, dan
mereka saling tersenyum, berpikir tentang
keciniaan Hana pada kemewahan dan
kedudukan. "Kurasa Ibu juga di sana."
"Ayo kita ke rumah lebih dulu," saran
Maya. "Bertemu Haruka dan Chiyo. Mereka
akan kirim pesan pada Ibu."
Maya menyadari kalau dirinya tidak yakin
akan reaksi ibunya. Tiba-tiba teringat dengan
penemuan terakhir mereka, kemarahan
Kaede, tamparan itu. Sejak saat itu, Maya tak
mendapat kabar apa pun dari ibunya, tidak
ada surat, tidak ada pesan. Bahkan kabar
tentang kelahiran adik laki-lakinya ia dengar
melalui Shigeko di Hofu. Aku bisa saja ikut
terbunuh bersama Sada dan Taku, pikirnya.
Ibu tidak akan peduli. Perasaan itu amat
menusuk hati dan mengganggunya: ia begitu
ingin pulang ke rumah, tapi kini takut pada
penerimaan ibunya. Andai Yuki adalah
ibuku, pikirnya. Aku bisa mengadu dan men-
ceritakan segalanya, dan dia pasti percaya.
Kesedihan yang mendalam menerpa
dirinya: bahwa Yuki sudah mati dan tidak
mengenal kasih sayang anaknya. Bahwa
Kaede hidup....
"Aku akan pergi," ujarnya. "Akan kulihat
siapa yang ada di sana, melihat apakah Ayah
sudah kembali."
"Ayah pasti belum kembali," sahut Miki.
"Ayah pergi jauh ke Miyako."
"Baiklah, Ayah justru lebih aman berada
jauh di sana ketimbang berada di rumah,"
sahut Maya. "Tapi kita harus ceritakan pada
Ibu tentang Paman Zenko, bagaimana dia
telah membunuh Taku dan tengah mem-
bangun kekuatan."
"Bagaimana dia bisa begitu berani saat
Hana dan kedua putranya ada di sini, di
Hagi?"
"Hana mungkin berencana membawa
mereka lari; itu sebabnya dia datang. Kau
tunggu di sini. Aku akan kembali secepat-
nya."
Maya masih mengenakan pakaian laki-laki
dan menu-rutnya tak ada orang yang bisa
mengenalinya. Banyak anak laki-laki seusia-
nya bermain di tepi sungai serta me-
manfaatkan pagar jaring penangkap ikan
untuk menyeberangi sungai. Gadis itu berlari
dengan langkah ringan di atasnya seperti
yang sudah sering dilakukannya: bagian atas
tiang pancang terasa lembap dan licin.
Setelah sampai di seberang, Maya berhenti di
depan lubang di dinding taman, tempat
aliran air mengalir ke sungai. Dengan meng-
gunakan kemampuan menghilang, Maya
melangkah masuk ke taman.
Seekor bangau abu-abu besar yang tengah
mencari ikan di sungai merasakan ada
gerakan, menoleh ke arah Maya kemudian
terbang. Kepakan sayapnya kedengaran
menghentak tajam seperti suara kibasan
kipas.
Di sungai, seekor ikan air tawar melompat.
Ikan itu mencipakkan air, dan burung itu
terbang dengan kepakan sayap pelan: tepat
seperti biasanya.
Maya berusaha mendengarkan suara-suara
di dalam rumah, begitu merindukan Haruka
dan Chiyo. Mereka pasti kaget, pikirnya. Dan
gembira. Chiyo pasti akan menangis bahagia
seperti biasanya. Maya seperti mendengar
suara mereka dari dapur.
Tapi di balik gumaman tadi terdengar
olehnya suara lain, berasal dari luar dinding
dari tepi sungai. Suara anak laki-laki,
berceloteh, tertawa.
Maya merendahkan tubuhnya di balik
batu paling besar sewaktu Sunaomi dan
Chikara mencepuk-cepuk air sungai. Di saat
yang sama, terdengar langkah kaki dari
dalam rumah, dan Kaede serta Hana berjalan
keluar menuju beranda.
Kaede menggendong bayi yang tersenyum
dan berusaha mencengkeram jubah ibunya.
Kaede mengangkatnya agar bisa melihat
kedua bocah yang datang menghampiri.
"Lihat, sayangku, mungilku. Lihatlah
sepupumu. Kau akan tumbuh besar menjadi
tampan seperti mereka!"
Si bayi tersenyum dan tersenyum lagi. Dia
sudah berusaha menggunakan kakinya dan
berdiri.
"Alangkah kotornya kalian, anak-anakku,"
Hana membentak mereka, wajahnya berseri-
seri dengan rasa bangga. "Cuci tangan dan
kaki kalian. Haruka! Bawakan air untuk
kedua tuan muda!"
Tuan muda! Maya mengamati Haruka
datang lalu mencuci kaki kedua bocah itu.
Dilihatnya rasa percaya diri dan keangkuhan
mereka berdua, melihat kasih sayang dan rasa
hormat yang mereka dapatkan tanpa ber-
susah payah dari semua perempuan di
sekeliling mereka.
Hana mengelitik si bayi dan membuatnya
tertawa cekikikan dan menggeliat-geliat.
Tatapan penuh kasih sayang terlukis di wajah
ibu dan bibinya.
"Bukankah sudah kukatakan," ujar Hana,
"Tidak ada yang bisa mengalahkan perasaan
memiliki anak laki-laki."
"Benar," sahui Kaede. "Aku tidak tahu
kalau aku bisa merasa seperti ini." Dipeluk-
nya bayi itu erat-erat, wajahnya nampak
gembira dengan perasaan cinta.
Maya merasakan kebencian yang tak
pernah dirasakan seumur hidupnya, seakan
hatinya hancur dan darah mendidih dalam
dirinya. Apa yang akan kulakukan? pikirnya.
Aku harus berusaha menemui Ibu tanpa ada
orang lain. Apakah Ibu mau mendengarkanku?
Apa seharusnya aku kembali pada Miki saja?
Pergi ke kastil menemui Lord Endo? Tidak,
aku harus menemui Ibu dulu. Tapi jangan
sampai Hana curiga kalau aku ada di sini
Maya menunggu tanpa suara di taman
sewaktu matahari terbenam. Kunang-kunang
menari di atas sungai, dan rumah berkilauan
dengan cahaya lentera. Ia mencium bau
makanan di ruangan di lantai atas, men-
dengar kedua bocah berbicara saat makan.
Kemudian pelayan muda membawa nampan
kembali ke dapur, dan tempat tidur digelar.
Kedua bocah itu tidur di bagian belakang
rumah, tempat para pelayan beristirahat saat
tugas mereka selesai. Hana dan Kaede tidur
di kamar atas bersama si bayi.
Saat rumah sudah sunyi, Maya mem-
beranikan diri masuk. Dilewatinya
nightingale floor tanpa suara karena sudah
begitu terbiasa. Ia berjingkat menaiki tangga
dan menyaksikan ibunya menyusui si bayi.
Maya merasakan kehadiran yang akrab di
sampingnya. Dia menengok ke belakang dan
melihat hantu perempuan itu, Yusetsu.
Prempuan itu tak lagi memakai jubah mantel
bertudung namun berpakaian putih orang
mati, seputih dagingnya. Napasnya terasa
dingin dan berbau tanah, dan perempuan itu
memandang pada si ibu dan anak dengan
tatapan iri yang begitu jelas terpancar di
wajahnya.
Kaede menyelimuti si bayi rapat-rapat lalu
membaringkannya.
"Aku harus menulis surat untuk suamiku,"
tuturnya pada Hana. "Panggil aku kalau
bayinya terbangun."
Kaede berjalan menuruni tangga menuju
bekas kamar Ichiro, tempat catatan dan alat
tulis disimpan, seraya memanggil Haruka
untuk membawakan lentera.
Sekarang aku harus menemui Ibu, pikir
Maya.
Hana duduk di sisi jendela yang terbuka,
menyisiri rambut panjangnya; sambil
menyenandungkan nina bobo untuk dirinya
sendiri. Lentera menyala di sebuah rak besi.
Hana bernyanyi:
Tulislah surat untuk suamimu,
Kakakku yang malang.
Dia tak akan menerima surat-suratmu.
Dia tidak layak mendapatkan cintamu.
Kau akan segera tahu
Laki-laki macam apa dia.
Alangkah beraninya dia bernyanyi seperti
itu, di rumah Ayahku! pikir Maya. Gadis itu
bimbang antara keinginan untuk menyerang
Hana saat itu juga atau ke bawah untuk
menemui ibunya.
Hana berbaring, kepalanya berada di atas
bantal kayu.
Aku bisa bunuh dia sekarang! pikir Maya,
sambil meraba pisaunya. Dia pantas mati!
Tapi kemudian bcrpikir kalau sebaiknya
membiarkan agar ayahnya yang menghukum
bibinya itu. Maya hendak keluar kamar
ketika si bayi menggeliat. Maya berlutut di
sampingnya. Bayi itu menangis pelan. Mata-
nya terbuka dan membalas tatapan Maya.
Dia bisa melihatku! pikirnya kaget. Maya
tak ingin si bayi benar-benar terbangun. Lalu
ia sadar kalau ia tak bisa berhenti menatap si
bayi. Maya tak bisa mengendalikan apa yang
sedang dilakukannya. Ditatap mata adiknya
dengan tatapan Kikuta, dan si bayi ter-
senyum satu kali ke arahnya lalu tertidur, dan
tidak pernah bangun lagi.
Yuki berkata di sampingnya, Ayo, kita bisa
pergi sekarang.
Seketika itu juga Maya memahami kalau
ini adalah bagian dari balas dendam
perempuan itu, balas dendam terhadap ibu-
nya, pembalasan keji atas kecemburuan yang
sudah sekian lama. Lalu menyadari kalau ia
telah melakukan tindakan yang tidak ter-
maafkan, bahwa tidak ada lagi tempat
baginya kecuali di dunia tempat para hantu
berkeliaran. Bahkan Miki pun tak akan bisa
menyelamatkannya saat ini. Dipanggilnya si
kucing dan dibiarkannya mengambil alih
dirinya, kemudian melompat menembus
dinding, berlari menyeberangi sungai, masuk
ke dalam hutan dan berpikir lagi, kembali ke
Hisao.
Yuki mengikutinya, melayang di atas
tanah, dengan hantu bayi dalam pelukan-
nya."*
Bayi laki-laki Kaede mati sebelum bulan
purnama pertengahan musim panas. Bayi
memang mudah mati, tidak ada orang yang
kaget: saat musim panas bayi mati karena
penyakit atau wabah, saat musim dingin
karena flu. Biasanya dianggap bijaksana
untuk tidak terlalu terikat pada anak-anak
karena sedikit yang bisa bertahan melewati
masa bayinya; Kaede berjuang mengendali-
kan dan membendung kesedihannya,
menyadari bahwa sebagai orang yang
mewakili ketidakhadiran suaminya, ia tidak
boleh patah semangat. Walau sebenarnya ia
lebih ingin mati. Direnungkanya berulang
kali apa kesalahannya hingga menyebabkan
kehilangan yang tak tertahankan ini. Apakah
ia memberi makan terlalu banyak. atau
terlalu sedikit; seharusnya ia tidak boleh
meninggalkan bayinya; ia sudah dikutuk,
pertama dengan kehadiran si kembar, lalu
dengan kematian ini. Sia-sia Tabib Ishida
berusaha meyakinkan bahwa mungkin saja
memang tidak ada alasannya, bahwa sudah
biasa bayi mati tanpa alasan yang jelas.
Kaede ingin sekali Takeo pulang, tapi juga
takut setengah mati untuk memberitahukan-
nya; merasa begitu ingin tidur bersamanya
lalu merasakan cinta mereka bisa menghibur
kesedihan hatinya seperti biasa. Namun ia
juga merasa tak kuasa bercinta dengan
suaminya karena tak sanggup menanggung
beban perasaan hamil hanya untuk ke-
hilangannya lagi.
Takeo harus diberi tahu, tapi bagaimana
melakukannya? Kaede bahkan tidak tahu di
mana suaminya. Butuh waktu berminggu-
minggu agar surat bisa sampai ke tangan
suaminya. Kaede belum mendapat kabar lagi
sejak suaminya mengirim surat dari Inuyama.
Setiap hari Kaede bertekad untuk menulis
surat, namun setiap hari pula ia tak kuasa
melakukannya. Sepanjang hari berharap agar
malam segera tiba supaya bisa melampiaskan
kesedihan dirinya. Dan sepanjang malam
tidak tidur, berharap matahari segera terbit,
agar bisa mengenyampingkan sedikit rasa
sakit di hatinya untuk sementara.
Satu-satunya yang bisa menghiburnya
adalah adik dan kedua keponakannya, yang
disayangi seperti anaknya sendiri. Ia bisa
menghabiskan banyak waktu bersama
mereka, mengawasi pelajaran mereka serta
menyaksikan pelatihan militer mereka. Si
bayi dimakamkan di Daishoin; bulan
semakin menyusut menjadi potongan kecil di
atas makamnya ketika kurir akhirnya datang
membawa pesan dari Takeo. Saat dibuka
gulungan kertasnya, sketsa burung karya
suaminya terjatuh. Dihaluskannya kertas itu
lalu menatapnya, goresan hitam seekor
burung gagak di atas bebatuan tebing,
burung tila serta bunga lonceng.
"Takeo menulis surat ini dari daerah kecil
bernama Sanda," tuturnya kepada Hana.
"Dia bahkan belum sampai ke ibukota."
Kaede melihat surat itu tanpa sungguh-
sungguh membacanya; mengenali tulisan
tangan Minoru, namun lukisan burung itu
Takeo sendiri yang menggambarnya: bisa
dilihatnya kekuatan dalam goresannya,
melihatnya menopang tangan kanan dengan
tangan kirinya, keahlian yang keluar dari
tangan cacatnya. Kaede hanya berdua dengan
Hana, kedua keponakannya berada di area
berkuda, para pelayan sibuk di dapur. Kaede
membiarkan air matanya jatuh berlinang.
"Dia tak tahu kalau putranya telah tiada!"
Hana berkata, "Kesedihannya tak berarti
apa-apa bila dibandingkan kesedihanmu.
Jangan menyiksa dirimu atas kesedihannya."
Hana memeluk Kaede lalu berbisik pelan
sekali. "Dia takkan bersedih. Dia justru akan
lega."
"Apa maksudmu?" Kaede agak menarik
tubuhnya lalu menatap adiknya. Dilihatnya
dengan tatapan nanar betapa cantiknya
Hana, dan menyesali bekas luka yang ia
derita. Namun tak satu pun dari semua itu
penting baginya. Dia rela terbakar lagi,
mencongkel kedua bola matanya kalau itu
bisa mengembalikan anaknya. Sejak
kematian anak laki-lakinya, Kaede amat
bergantung pada Hana, menying-kirkan
kecurigaan, hampir lupa bahwa Hana dan
kedua putranya berada di Hagi sebagai
sandera.
"Aku sedang memikirkan ramalan itu."
"Ramalan apa?" tanya Kaede seraya meng-
ingat ketika di Inuyama saat ia dan Takeo
tidur bersama, kemudian berbicara tentang
kata-kata yang mengendalikan hidup mereka
berdua. "Ramalan tentang Lima Per-
tempuran? Apa hubungannya dengan
ramalan itu?" Ia tak ingin membicarakan
tentang ramalan itu saat ini, tapi ada sesuatu
di dalam nada bicara Hana yang membuat-
nya ketakutan. Hana tahu sesuatu yang tidak
diketahuinya. Kendati cuaca terasa panas,
tubuhnya terasa dingin, gemetar.
"Ada kata-kata lain dalam ramalan itu,"
tutur Hana. "Apakah Takeo tidak mengata-
kannya?"
Kaede menggeleng, benci untuk
mengakuinya. "Bagaimana kau bisa tahu?"
"Takeo mengutarakan pada Muto Kenji,
dan kini telah diketahui luas di kalangan
Tribe."
Kaede merasakan kilatan amarah dalam
dirinya. Ia selalu merasa benci dan takut pada
kehidupan rahasia Takeo: suaminya pernah
meninggalkan ia bersama Tribe, meninggal-
kan ia dengan anaknya yang akhirnya
meninggal dan dirinya sendiri sekarat.
Kebencian lama berkecamuk lagi dalam
dirinya. Kaede menyambut perasaan itu
karena bisa membantunya menyembuhkan
kesedihannya.
"Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya."
"Bahwa Takeo selamat dari kematian,
kecuali di tangan putra kandungnya."
Selama beberapa saat Kaede tak bereaksi.
Tahu kalau Hana tidak berbohong kepada-
nya: ia tahu bagaimana Takeo dibentuk oleh
ramalan ini, ketidaktakutannya serta tekad-
nya yang kuat. Dan Kaede memahami
kelegaan Takeo saat semua anak mereka
perempuan.
"Semestinya dia mengatakannya kepadaku,
tapi dia ingin melindungiku," tuturnya. "Aku
tak percaya dia akan senang atas kematian
anaknya. Aku mengenalnya lebih baik dari
itu." Rasa lega menyelimuti dirinya: semula
ia takut sesuatu yang lebih buruk akan
dikatakan Hana.
"Ramalan adalah hal yang berbahaya,"
ujarnya. "Sekarang yang satu ini tidak
mungkin menjadi kenyataan. Putranya sudah
mendahului dirinya, dan takkan ada anak
lagi."
Takeo akan kembali kepadaku, pikirnya,
seperti yang senantiasa dilakukannya. Dia
takkan mati di wilayah Timur. Bahkan
mungkin sekarang dia dalam perjalanan
pulang.
"Semua orang berharap Lord Takeo ber-
umur panjang dan bahagia," ujar Hana.
"Mari kita doakan kalau ramalan ini tidak
mengacu ke putranya yang lain."
Ketika Kaede menatapnya tanpa bicara,
Hana melanjutkan kata-katanya, "Maaf, kak,
kukira kau sudah tahu."
"Ceritakan," kata Kaede tanpa perasaan.
"Aku tak bisa menceritakannya. Bila hal
ini dirahasiakan suamimu...."
"Ceritakan," ulang Kaede, dan mendengar
suaranya pecah.
"Aku sangat takut bisa membuatmu lebih
sakit hati. Biar Takeo yang menceritakan saat
dia kembali nanti."
"Dia punya anak laki-laki?"
"Ya," sahut Hana sambil menarik napas.
"Anak itu berusia tujuh betas tahun. Ibunya
adalah Muto Yuki."
"Putrinya Kenji?" tanya Kaede lirih. "Jadi
selama ini Kenji tahu?"
"Kurasa begitu. Sekali lagi, hal ini bukan
rahasia di kalangan Tribe."
Shizuka, Zenko, Taku? Mereka semua
tahu hal ini selama bertahun-tahun
sementara ia sama sekali tidak tahu? Tubuh
Kaede gemetar.
"Kau sakit," ujar Hana dengan penuh
perhatian. "Biar kuambilkan teh. Perlu
kupanggilkan Ishida?"
"Mengapa Takeo tidak mengatakan
padaku?" tanya Kaede. Ia tidak terlalu marah
pada ketidaksetiaan suaminya; malah merasa
agak cemburu pada perempuan yang sudah
mati bertahun-tahun lalu; tapi hatinya
hancur karena merasa ditipu habis-habisan.
"Andai Takeo mengatakannya padaku."
"Kurasa dia ingin melindungimu," ujar
Hana.
"Berita itu hanyalah kabar burung," kata
Kaede.
"Tidak, aku pernah bertemu anak itu. Aku
melihatnya beberapa kali di Kumamoto. Dia
seperti kebanyakan orang Tribe, tidak jujur
dan kejam. Kau takkan percaya kalau anak
itu adalah kakak tiri Shigeko."
Kata-kata Hana menikam dirinya lagi.
Diingatnya lagi semua hal yang ia cemaskan
tentang Takeo selama mereka bersama:
kekuatan aneh, darah campuran, kekuatan
aneh yang diturunkan dalam diri si kembar.
Kesedihan lalu kekagetannya atas rahasia
yang baru terungkap ini mengacaukan segala
yang telah dijalani dalam hidup. Kaede
membenci Takeo: membenci dirinya sendiri
karena telah mengabdikan hidupnya pada
suaminya; menyalahkan suaminya atas semua
penderitaan yang ia alami, kelahiran terkutuk
si kembar, kematian bayi laki-laki yang amat
disayanginya. Kaede ingin menyakiti, me-
rampas segalanya dari Takeo.
Disadarinya kalau tangannya masih
memegang sketsa tadi. Burung-burung itu
mengingatkannya dengan kebe-basan, seperti
biasanya, tapi itu hanyalah ilusi. Burung
tidak lebih bebas ketimbang manusia, sama
terikatnya dengan rasa lapar, hasrat, serta
kematian. Ia terikat selama hampir separuh
hidupnya pada laki-laki yang telah meng-
khianati dirinya, yang tidak pernah layak
mendapatkan dirinya. Dirobek-robek sketsa
itu hingga hancur kecil-kecil lalu diinjak-
injak.
"Aku tak bisa tinggal di sini. Apa yang
harus kulakukan?"
"Ikutlah dengaku ke Kumamoto," ajak
Hana. "Suamiku akan mengurusmu."
Kaede teringat pada ayah Zenko yang
telah dijadikan musuhnya, semuanya demi
Takeo.
"Betapa bodohnya aku selama ini,"
tangisnya. Tenaga baru menyeruak dari
dalam dirinya. "Panggil kedua anakmu dan
siapkan mereka untuk melakukan per-
jalanan," pintanya pada Hana. "Berapa
banyak pengawal yang ikut bersamamu?"
"Tiga atau empat puluh," sahut Hana.
"Mereka menginap di kastil."
"Pengawalku juga menginap di sana," ujar
Kaede. "Pengawal yang tidak ikut dengannya
ke wilayah Timur." Kaede tak sanggup
mengucapkan kata suamiku maupun
menyebut namanya. "Kita akan membawa
mereka semua, tapi suruh sepuluh pengawal-
mu datang ke sini. Ada tugas untuk mereka.
Kita akan pergi sebelum akhir minggu ini."
"Terserah kau, kak," ujar Hana setuju.*
Sudah semalaman di tepi sungai Miki
menunggu Maya kembali. Saat matahari
terbit dia menduga kalau saudara kembarnya
itu sudah pergi ke alam baka, tempat ia tidak
bisa mengikuri. Lebih dari segalanya, Miki
ingin pulang ke rumah; ia lelah dan lapar,
dan bisa dirasakannya kekuatan si kucing
meyerap semua tenaganya. Tapi ketika tiba
di gerbang rumah di tepi sungai, terdengar
olehnya jeritan kesedihan, disadarinya kalau
adik bayinya sudah meninggal malam itu.
Kecurigaan yang amat dalam semakin besar
dalam dirinya, memenuhi dirinya dengan
ketakutan yang amat sangat. Miki meringkuk
di luar dinding, menutupi kepala dengan
tangan, takut masuk ke dalam tapi tidak tahu
harus ke mana.
Salah satu pelayan bergegas melewati
dirinya tanpa mengenalinya, dan tak lama
kemudian kembali bersama tabib Ishida yang
nampak terkejut dan pucat. Tak satu pun
dari mereka bicara kepada Miki, tapi mereka
pasti telah melihat dirinya, karena tidak lama
setelah itu Haruka keluar dan meringkuk di
sebelahnya.
"Maya? Miki?"
Miki melihat air mata yang mulai ber-
linang di pipinya. Ia ingin mengatakan
sesuatu, tapi tidak berani bicara, kalau-kalau
ia menyuarakan apa yang dicurigainya.
"Demi Surga, apa yang kau lakukan di
sini? Kau Miki, kan?"
Gadis itu mengangguk.
"Ini waktu yang buruk," ujar Haruka,
menangisi dirinya sendiri. "Masuklah, nak.
Lihatlah dirimu, lihat keadaanmu. Apa kau
tinggal di hutan seperti hewan liar?"
Cepat-cepat Haruka menuntunnya masuk
ke dalam rumah, tempat Chiyo, dengan
wajah yang juga basah dengan air mata,
tengah menjaga api. Chiyo memekik ter-
kejut, dan mulai menggumamkan sesuatu
tentang nasib buruk dan kutukan.
"Jangan diteruskan," ujar Haruka. "Ini
bukan salahnya."
Ketel besi menggantung di atas api
mengeluarkan bunyi berdesis, dan uap serta
asap memenuhi udara. Haruka membawa
sebaskom air lalu membasuh wajah, tangan
dan kaki Miki. Air hangat membuat semua
luka dan lecetnya terasa perih.
"Kami akan menyiapkan air mandi untuk-
mu," kata Haruka. "Tapi kau harus makan
dulu." Ditaruhnya nasi di mangkuk lalu
menuangkan kaldu di atasnya. "Alangkah
kurusnya dia!" katanya ke samping, ke arah
Chiyo. "Perlukah kuberitahu ibunya kalau
dia di sini?"
"Sebaiknya tidak usah," sahut Chiyo.
"Jangan dulu. Nanti malah membuatnya
semakin kesal."
Tangis Miki terlalu keras untuk mem-
buatnya bisa makan, napasnya tersengal-
sengal dengan isak tangis.
"Bicaralah, Miki," desak Haruka padanya.
"Kau akan merasa lebih baik. Tidak ada
masalah yang terlalu berat hingga tak bisa
diceritakan."
Sewaktu Miki menggelengkan kepala
tanpa bicara, Haruka berkata, "Dia seperti
ayahnya ketika pertama kali datang ke rumah
ini. Dia tidak bicara selama berminggu-
minggu."
"Pada akhirnya dia bicara juga," gumam
Chiyo. "Rasa terguncang membungkam
mulutnya, lalu perasaan itu pula yang
membuka mulutnya."
Beberapa saat kemudian tabib Ishida
datang untuk bicara dengan Chiyo agar
menyeduh teh khusus untuk membantu
Kaede tidur.
"Tabib, lihat siapa yang ada di sini," kata
Haruka, seraya menunjuk Miki yang masih
meringkuk di salah satu sudut dapur dengan
wajah pucat dan badan gemetar.
"Ya, tadi aku melihatnya," sahut Ishida
kebingungan. "Jangan biarkan dia dekat-
dekat dengan ibunya. Lady Otori sedang
bersedih. Bila makin tertekan maka dia bisa
gila. Kau akan bertemu setelah ibumu lebih
baikan," katanya pada Miki dengan nada
agak tegas. "Sementara ini kau jangan meng-
ganggu siapa pun. Kau boleh memberinya
teh yang sama, Haruka; teh itu bisa
menenangkannya."
Miki dikurung di gudang terpencil selama
beberapa hari berikutnya. Didengarnya
suara-suara di dalam rumah di sekitarnya
karena pendengaran Kikutanya makin peka.
Didengarnya Sunaomi dan Chikara saling
berbisik, sedih tapi sekaligus gembira dengan
kematian sepupu kecil mereka. Didengarnya
percakapan antara ibunya dan Hana, serta
ingin sekali berlari menghampiri dan meng-
halangi mereka, namun tak berani membuka
mulut. Didengarnya tabib Ishida dengan sia-
sia mengajukan keberatan pada ibunya, lalu
mengatakan kepada Haruka kalau dia akan
pergi ke Inuyama untuk bertemu dengan
ayahnya.
Bawa aku bersamamu, Miki ingin berseru
memanggilnya, tapi Ishida pergi dengan
terburu-buru, mencurahkan perhatiannya
pada banyak persoalan: Kaede, istrinya
sendiri, Shizuka, juga Takeo. Ia tak ingin
dibebani oleh seorang anak yang bisu dan
tidak sehat.
Miki punya waktu yang banyak dalam
kesunyian dan kesendirian, dengan
penyesalan, perjalanan bersama Yuki dan
tuntutan balas dendam perempuan itu pada
ibunya. Ia merasa kalau dirinya sudah tahu
sejak lama tujuan Yuki yang sebenarnya, dan
kalau seharusnya ia bisa mencegahnya. Kini
ia kehilangan semuanya: saudara kembarnya,
ibunyadan setiap malam memimpikan
ayahnya dan takut kalau ia takkan bertemu
ayahnya lagi.
Dua hari setelah kepergian Ishida, Miki
mendengar suara pengawal dan kuda di
jalanan. Ibunya, Hana dan kedua putranya
bersiap pergi.
Terjadi adu mulut keras antara Haruka
dan Chiyo tentang dirinya. Haruka berkata
kalau Miki harus bertemu ibunya sebelum
pergi, Chiyo menyahut kalau suasana hati
Kaede sangat rapuh; tak bisa diduga akan
bagaimana reaksinya nanti.
"Tapi ini putrinya!" sahut Haruka dengan
jengkel.
"Apa artinya seorang putri baginya? Dia
sudah kehilangan putranya; dia di ambang
kegilaan," sahut Chiyo.
Miki diam-diam masuk ke dapur dan
Haruka menggandeng tangannya. "Kita akan
menyaksikan kepergian ibumu," bisiknya.
"Tapi jangan sampai terlihat."
Jalanan penuh dengan orang, berkerumun
dengan perasaan kegelisahan yang terlihat
samar. Telinga Miki yang tajam menangkap
potongan kata-kata yang mereka lontarkan.
Lady Otori meninggalkan kota bersama Lady
Arai. Lord Otori tewas di wilayah Timur.
Bukan, bukan tewas tapi kalah dalam
pertempuran. Lord Otori akan diasingkan,
dan putrinya ada bersamanya....
Miki memerhatikan selagi ibunya dan
Hana keluar dari rumah lalu menaiki kuda
yang menunggu di luar gerbang. Sunaomi
dan Chikara diangkat menaiki kuda poni
mereka. Pengawal membawa lambang
Shirakawa dan Arai mengelilingi mereka.
Sewaktu rombongan mulai berjalan, Miki
berusaha menangkap tatapan mata ibunya,
namun Kaede menatap lurus ke depan, tidak
melihatnya. Ibunya bicara satu kali. Sepuluh
orang atau lebih prajurit pejalan kaki berlari
memasuki taman; sebagian memegang obor
yang menyala, sedang yang lainnya me-
megang jerami dan potongan kayu kecil
untuk menyalakan api. Dengan sigap dan
tangkas, mereka membakar rumah itu.
Chiyo berlari keluar dan menghalangi
mereka, memukuli mereka dengan tinjunya
yang lemah. Mereka mendorong dengan
kasar; menghempaskan tubuh Chiyo ke atas
beranda, yang kemudian memeluk erat salah
satu tiang, seraya menangis, "Ini rumah Lord
Shigeru. Beliau takkan memaafkan kalian."
Mereka tidak bersusah payah menyingkir-
kan perempuan tua itu, namun dengan
ringannya menumpuk jerami di sekitar
tubuh Chiyo. Haruka menjerit-jerit di
sampingnya. Miki menatap ketakutan, asap
membuat matanya pedih dan mengeluarkan
air mata saat nightingale floor bernyanyi
untuk yang terakhir kalinya. Ikan-ikan merah
dan emas terebus di dalam kolam, benda-
benda seni yang berharga dan catatan di
dalam rumah itu meleleh dan mengerut.
Rumah yang bertahan meski diguncang
gempa, banjir dan perang luluh lantak
dimakan api, bersama Chiyo yang menolak
untuk meninggalkannya.
Kaede berjalan ke kastil tanpa menengok.
Kerumunan orang hanyut mengikutinya,
membawa Haruka dan Miki bersama
mereka. Di sini pengawal Hana telah
menunggu, bersenjata dan juga membawa
jerami dan obor. Pimpinan pengawal, Endo
Teruo, yang ayahnya menyerahkan kastil
kepada Takeo dan tewas terbunuh di
jembatan batu oleh anak buah Arai Daiichi,
datang menghampiri gerbang.
"Lady Otori," ujarnya. "Apa yang terjadi?
Kumohon Anda mendengarkanku. Mari
masuk ke dalam. Mari kita bicarakan duduk
persoalannya."
"Aku bukan lagi Lady Otori," sahutnya.
"Aku Shirakawa Kaede. Aku berasal dari
Klan Seishuu dan aku akan kembali kepada
klanku. Tapi sebelum pergi, aku perintah-
kan kau serahkan kastil kepada pengawal-
pengawal ini."
"Aku tidak tahu apa yang telah terjadi
pada Anda," sahutnya. "Tapi aku akan mati
lebih dulu sebelum menyerahkan kastil Hagi
saat Lord Otori tidak ada di sini."
Laki-laki itu menarik pedang. Kaede
menatap gusar. "Aku tahu seberapa
sedikitnya anak buahmu yang tersisa,"
ujarnya. "Yang tersisa hanyalah pengawal
yang sudah tua dan yang masih sangat muda.
Dan aku mengutukmu, kota Hagi dan
seluruh Klan Otori."
"Lady Arai," seru Endo pada Hana. "Aku
membesarkan suami Anda di rumahku
bersama dengan putra kandungku sendiri.
Jangan biarkan pengawal Anda melakukan
kejahatan ini!"
"Bunuh dia," ujar Hana, dan pengawal
merangsek ke depan. Endo tidak memakai
baju zirah, dan para penjaganya tidak siap.
Kaede benar: kebanyakan dari mereka masih
anak-anak. Kematian mereka yang tiba-tiba
membuat kerumunan orang ketakutan;
orang-orang mulai melempar batu ke arah
prajurit Arai dan dibalas dengan pedang dan
tombak terhunus. Kaede dan Hana
membelokkan kuda lalu berderap pergi ber-
sama pendamping mereka sementara sisa
pengawal yang tinggal mulai membakar
kastil.
Saat pasukan Arai melarikan diri, orang-
orang berjuang memadamkan atau menahan
meluasnya api dengan berember air, tapi
angin kencang berhembus dari laut; percikan
api melahap atap dengan dahan kering yang
mudah terbakar dan api segera saja melalap
cepat, tak bisa dicegah. Penduduk kota
berkumpul di jalan, di pantai dan sepanjang
tepi sungai, tanpa bicara karena terkejut.
Mereka tidak sanggup memahami apa yang
telah terjadi, betapa kehancuran telah
menyerang di jantung Hagi, merasakan
bahwa keselarasan telah sirna dan kedamaian
telah berakhir.
Haruka dan Miki menghabiskan malam
itu di tepi sungai bersama ribuan orang
lainnya. Keesokan harinya mereka bergabung
dengan orang-orang yang melarikan diri dari
kota yang tengah ditalap api. Mereka
menyeberangi jembatan, berjalan pelan agar
Miki punya banyak waktu untuk membaca
tulisan di jembatan.
Klan Otori menyambut keadilan dan kesetiaan.
Waspadalah ketidakadilan dan ketidaksetiaan.
Kala itu hari kesembilan di bulan
ketujuh.*
"Ijinkan aku ikut dengan Lord Otori,"
Minoru memohon selagi Takeo bersiap pergi
ke Yamagata.
"Aku lebih senang kau tinggal di sini,"
sahut Takeo. "Keluarga dari korban yang
tewas harus diberitahu, dan persediaan
makanan disiapkan untuk perjalanan panjang
berikutnya: Kahei harus membawa pasukan
utama kita ke wilayah Barat. Dan selain itu
ada tugas khusus untukmu," tambahnya,
menyadari kekecewaan pemuda itu.
"Tentu saja, Lord Otori," ujar si juratulis,
memaksakan diri tersenyum. "Namun, aku
punya satu permintaan. Kuroda Junpei
menantikan Anda kembali. Maukah Anda
ijinkan dia mendampingi Anda? Aku sudah
berjanji akan memohon kepada Anda."
"Jun dan Shin masih di sini?" tanya Takeo
kaget. "Kukira mereka sudah kembali ke
Barat."
"Sepertinya tak semua orang senang
dengan Zenko," gumam Minoru. "Aku
curiga, Anda akan menemukan banyak dari
mereka yang masih setia kepada Anda."
"Apakah itu resiko yang harus kuambil?"
Takeo bertanya pada diri sendiri, dan
menyadari kalau ia tidak terlalu peduli
dengan jawabannya. Ia sudah hampir mati
rasa dengan kesedihan dan kelelahan,
kecemasan dan rasa sakit. Berulang kali
belakangan sejak Ishida menyampaikan kabar
buruk itu, dirasakannya seperti berhalusinasi,
dan kata-kata Minoru selanjutnya pun
menambah perasaannya menjadi semakin
tidak nyata.
"Hanya Jun yang masih di sini, Shin di
Hofu."
"Mereka memisahkan diri? Aku tidak
mengira kalau hal itu bisa terjadi."
"Tidak, mereka memutuskan kalau salah
satu harus pergi, dan yang lainnya haras tetap
di sini. Mereka berbagi tugas. Shin ke Hofu
untuk melindungi Shizuka, sedangkan Jun
tinggal di sini untuk melindungi Anda."
"Aku mengerti." Ishida menceritakan
sedikit tentang Shizuka: bagaimana kabar
yang tersiar mengatakan kalau perempuan itu
sudah gila setelah kematian putranya dan
duduk di pelataran kuil Daifukuji, ditopang
oleh Surga. Pikiran kalau Shin yang tenang
dan tidak banyak bicara mengawasi Shizuka
membuatnya terharu.
"Kalau begitu Jun boleh ikut denganku,"
katanya. "Sekarang, Minoruaku meng-
andalkanmu untuk mencatat kejadian yang
sebenarnya tentang perjalanan kita ke
Miyako, janji Lord Saga, provokasi yang
telah menyebabkan perang, serta ke-
menangan kita. Putriku, Lady Maruyama,
akan segera sampai di sini. Aku menugas-
kanmu untuk melayaninya sesetia kau
melayaniku. Aku akan mendiktekan surat
wasiatku kepadamu. Aku tak tahu apa yang
akan terjadi padaku kelak, tapi aku mem-
perkirakan hal yang terburuk: entah itu ber-
bentuk pengasingan diri atau pun kematian.
Aku menyerahkan semua kekuasaan dan
wewenang atas Tiga Negara pada putriku.
Akan kukatakan kepadamu siapa yang akan
dinikahinya dan apa saja syaratnya."
Dokumen itu didiktekan dan ditulis
dengan cepat. Saat sudah selesai dan mem-
bubuhkan capnya, Takeo berkata, "Kau
harus berikan ini langsung ke tangan Lady
Shigeko. Kau bisa katakan kepadanya kalau
aku minta maaf. Aku berharap segalanya bisa
terjadi sebaliknya, namun aku memercayakan
Tiga Negara kepadanya."
Selama bertahun-tahun mengabdi pada
Takeo, Minoru jarang menunjukkan perasa-
annya. Dia telah menghadapi kemegahan
istana Kaisar dan kebiadaban perang dengan
sikap acuh tak acuh. Kini wajahnya
menyeringai selagi berjuang agar air matanya
tidak menetes.
"Katakan pada Lord Gemba aku sudah
siap pergi," kata Takeo. "Selamat tinggal."
***
Hujan terlambat turun dan tidak sederas
biasanya; setiap sore terjadi badai sebentar
dan langit kerapkali berawan, tapi jalanan
tidak banjir. Kini Takeo bersyukur telah
membangun jalan raya di seluruh Tiga
Negara sehingga perjalanannya bisa secepat
sekarang ini. Meski, pikirnya, jalanan yang
sama terbuka bagi Zenko dan pasukannya, dan
ingin tahu sudah seberapa jauh mereka
mendahului dari arah barat daya.
Pada malam ketiga, mereka menyeberangi
perbatasan di Kushimoto dan berhenti untuk
makan dan beristirahat sebentar di peng-
inapan di ujung lembah. Jaraknya kurang
dari satu hari dari Yamagata. Penginapan itu
dipenuhi pelancong; pemilik tanah daerah
setempat yang mengetahui kedatangan Takeo
langsung menghampiri untuk menyapa. Saat
ia makan, laki-laki ini, Yamada, dan si
pemilik penginapan menyampaikan kabar
yang mereka dengar.
Zenko dilaporkan berada di Kibi, tepat di
seberang sungai.
"Dia membawa sedikitnya sepuluh ribu
pasukan," tutur Yamada murung. "Banyak di
antara mereka yang membawa senjata api."
"Apakah ada kabar dari Terada?" tanya
Takeo, seraya berharap kapal-kapalnya
mungkin melakukan serangan balasan di
kota kastil Zenko, Kumamoto, dan
memaksanya untuk mundur.
"Kabarnya Zenko mendapatkan kapal dari
kaum bar-bar," lapor si pemilik penginapan,
"dan mereka melindungi pelabuhan dan
daerah pesisir pantai."
Takeo membayangkan pasukannya ke-
habisan tenaga, serta masih berjarak sepuluh
hari berjalan kaki.
"Lady Miyoshi tengah menyiapkan
Yamagata untuk pengepungan," tutur
Yamada. "Aku sudah mengirim dua ratus
pasukan ke sana, tapi tidak menyisakan satu
pun orang di sini; panen sudah hampir tiba,
dan sebagian besar ksatria Yamagata berada
di wilayah Timur bersama Lord Kahei. Kota
akan dipertahankan oleh petani, perempuan
dan anak-anak."
"Tapi sekarang Lord Otori sudah di sini,"
ujar si pemilik penginapan, berusaha mem-
bangkitkan semangat semua orang. "Negara
Tengah aman dengan adanya Lord Otori
bersama kita!"
Takeo berterima kasih padanya dengan
senyum seraya menyembunyikan keputus-
asaannya yang kian meningkat. Kelelahan
membuatnya tertidur; lalu menunggu
dengan gelisah dan tidak sabar sampai
matahari terbit. Saat itu awal bulan, terlalu
gelap untuk bisa berkuda di malam hari
tanpa cahaya bulan.
Mereka berada di jalan lagi, tak lama
setelah matahari terbit, bergerak dengan
cepat. Langit masih kelabu dan udara terasa
tenang, lereng pegunungan memamerkan
kibaran panji-panji besar mereka di tengah
kabut. Dua prajurit berkuda berderap
menghampiri dari arah Yamagata. Takeo
mengenali salah satunya sebagai putra
bungsu Kahei, pemuda berusia tiga belas
tahun; sedang yang lainnya pengawal tua dari
Klan Miyoshi.
"Kintomo! Ada kabar apa?"
"Lord Otori!" seru pemuda itu terengah-
engah. Wajahnya pucat karena kaget, dan
tatapan matanya bingung di bawah topi
bajanya. Topi dan baju zirahnya tampak ke-
dodoran karena dia baru memasuki masa
dewasa. "Istri Anda, Lady Otori...."
"Teruskan," perintah Takeo saat bocah itu
terbata-bata.
"Beliau datang dua hari lalu, mengambil
alih perintah di sana, lalu berniat menyerah-
kannya pada Zenko yang saat ini sedang
berjalan dari Kibi."
Pandangan Kintomo beralih ke Gemba
lalu berkata dengan rasa lega, "Pamanku ada
di sini!" Tak lama kemudian air mata
mengambang di pelupuk matanya.
"Bagaimana dengan ibumu?" tanya
Gemba.
"Ibu berusaha bertahan dengan sisa
pasukan yang ada. Sewaktu sudah tak ber-
daya lagi, ibu menyuruhku pergi selagi masih
sempat, untuk memberitahu ayah dan kakak-
kakakku. Kurasa ibu akan mencabut
nyawanya sendiri, juga kakak-kakak
perempuanku."
Takeo membelokkan kuda, tak mampu
menyembunyikan kekagetan dan ke-
bingungannya. Istri dan putri Kahei sudah
mati, sementara suami dan ayah mereka ber-
tempur mempertahankan Tiga Negara?
Yamagata, permata Negara Tengah, akan
diserahkan kepada Zenko oleh Kaede?
Gemba mendekat ke sampingnya, dan
menanti Takeo bicara.
"Aku harus bicara dengan istriku," ujar
Takeo. "Pasti ada penjelasannya. Kesedihan
dan kesepian telah membuatnya gila. Tapi
begitu aku ada bersamanya, akal sehatnya
akan kembali. Aku takkan ditolak untuk
memasuki Yamagata. Kita semua akan ke
sanasemoga sempat menyelamatkan
ibumu," imbuhnya kepada Kintomo.
Jalanan dipenuhi orang yang melarikan
diri dari kota untuk menghindari pe-
perangan. Hal ini melambatkan perjalanan
mereka, serta menambah kemarahan dan
keputus-asaan Takeo. Ketika mereka tiba di
Yamagata pada sore harinya, gerbang
kastilnya dipalang. Utusan pertama yang
mereka kirim ditolak masuk, sedangkan
utusan yang kedua dipanah begitu masuk
dalam jangkauan tembakan.
"Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan
sekarang," ujar pengawal Miyoshi sewaktu
mereka menarik diri berlindung masuk ke
hutan. "Ijinkan aku membawa tuan muda
kepada ayahnya, Zenko akan tiba di sini
besok. Lord Otori seharusnya juga mundur
bersama kami. Jangan sampai tertangkap."
"Kalian boleh pergi," ujar Takeo. "Aku
akan tinggal lebih lama lagi."
"Kalau begitu aku akan menemanimu,"
kata Gemba. Dipeluknya keponakannya.
Takeo memanggil Jun dan menyuruhnya
mendampingi Kintomo dan menjaganya
sampai bergabung dengan Kahci.
"Ijinkan aku menemani Anda," ujar Jun
dengan sikap canggung. "Aku bisa masuk ke
dalam dinding setelah malam tiba dan
membawa pesan Anda kepada...."
"Terima kasih, tapi hanya aku yang bisa
menyampaikan pesan ini. Sekarang aku
perintahkan kau pergi."
"Aku akan mematuhi Anda, begitu tugas
ini selesai, aku akan bergabung dengan Anda:
dalam keadaan hidup bila memungkinkan;
bila tidak, dalam kematian!"
"Kalau begitu sampai jumpa lagi," sahut
Takeo. Dipujinya Kintomo atas keberanian
dan kesetiaannya, dan memerhatikan selama
beberapa saat ketika bocah itu bergabung
bersama kerumunan orang yang melarikan
diri ke wilayah Timur.
Lalu dialihkannya lagi perhatian kembali
ke kota. Ia dan Gemba berkuda sedikit
mengitari sisi timur, berhenti di pepohonan.
Takeo turun dari Ashige lalu menyerahkan
tali kekang pada Gemba.
"Tunggu di sini. Bila aku tak kembali,
baik itu malam ini, atau kalau aku berhasil
melewati gerbang yang dibuka esok pagi, kau
anggap saja aku sudah mati. Bila me-
mungkinkan, makamkan aku di Terayama,
di samping makam Shigeru. Dan simpan
pedangku di sana untuk putriku!"
Sebelum membalikkan badan, Takeo
menambahkan, "Dan kau bisa melakukan
kegiatan berdoamu itu untukku, bila kau
mau."
"Aku tak pernah berhenti melakukannya,"
ujar Gemba.
***
Ketika malam tiba, Takeo meringkuk di
bawah pepohonan dan menatap dinding
yang melingkari kota. Teringat pada suatu
senja di musim semi, bertahun-tahun silam,
sewaktu Matsuda Shingen mengujinya
dengan pertanyaan teoritis: bagaimana meng-
ambil alih kota Yamagata? Kala itu dipikirnya
cara yang terbaik yaitu memasuki kastil
secara diam-diam lalu membunuh
pemimpinnya. Ia pernah memasuki kastil
Yamagata sebagai Tribe, kini ia melihat
apakah ia bisa melakukannya, ingin tahu
apakah ia sanggup membunuh. Ia pernah
membunuh orang, dan masih ingat rasa
bersalah, tanggung jawab dan penyesalan.
Akan dimanfaatkannya bagian kecil dari
pengetahuannya tentang kota dan kastil ini
untuk yang terakhir kalinya.
Di belakangnya terdengar kuda sedang
mengunyah rumput, dan Gemba ber-
senandung dengan gayanya yang seperti
beruang. Burung malam pemakan serangga
mengetuk-ngetuk di pohon. Angin berdesir
sejenak lalu tenang.
Bulan baru dari bulan kedelapan ber-
gelayut di atas pegunungan di sebelah
kanannya. Bisa dilihatnya gelapnya kastil
langsung ke arah utara. Di atasnya rasi
bintang beruang bermunculan di lembutnya
langit musim panas.
Dari dinding yang mengelilingi kota dan
gerbang, bisa didengamya suara para penjaga:
pasukan Shirakawa, dan Arai, dengan aksen
bicara dari wilayah Barat.
Bersembunyi di balik kegelapan, Takeo
melompat ke puncak dinding, sedikit salah
perhitungan, mencengkeram atapnya. Sesaat
lupa dengan luka di bahu kanannya yang
baru setengah sembuh, dan menahan napas
menahan sakit ketika luka itu menganga lagi.
Bunyi akibat gerakannya terdengar lebih
gaduh dari yang diinginkannya. Ia lalu
menyejajarkan diri tanpa terlihat di atas atap.
Ada dua orang yang muncul di bawahnya
membawa obor yang menyala. Mereka
berjalan menyusuri jalanan lalu kembali lagi,
sementara ia menahan napas dan mencoba
mengacuhkan rasa sakit, menekuk sikutnya
di atas puncak atap, menekan bahu kanan
dengan tangan kiri. Ia merasakan sedikit
lembap saat darah mengalir dari lukanya,
beruntung tak banyak sehingga tidak
menetes yang bisa mengakibatkan dirinya
tertangkap.
Kedua penjaga itu kembali ke tempatnya.
Takeo menjatuhkan diri ke permukaan
tanah, kali ini tanpa bersuara, dan mulai
berjalan menelusuri jalanan menuju kastil.
Malam semakin larut, tapi suasana kota jauh
dari sunyi. Orang-orang berkerumun dengan
cemas, banyak yang hendak pergi begitu
gerbang dibuka. Didengarnya para pemuda-
pemudi mengatakan bahwa mereka akan
melawan pasukan Arai dengan tangan
kosong, bahwa Yamagata takkan dirampas
dari Otori lagi; didengarnya para pedagang
meratapi berakhirnya kedamaian dan
kemakmuran; para perempuan mengutuk
Lady Otori karena telah menyebabkan
perang. Hatinya hancur mengingat Kaede.
bahkan di saat dirinya tengah mencari pen-
jelasan tentang mengapa istrinya bertindak
seperti ini. Kemudian ia mendengar orang-
orang berbisik, '"Perempuan itu membawa
kematian bagi semua yang menginginkan
dirinya, dan kini dia akan membawa
kematian pada suaminya, begitu pula dengan
suami dan anak laki-laki kita."
Tidak, Takeo ingin menjerit lantang.
Tidak untuk diriku. Kaede tidak bisa
membawa diriku pada kematian. Tapi ia
takut kalau istrinya memang sudah melaku-
kannya.
Takeo berjalan melewati mereka tanpa
terlihat. Di tepi parit besar ia meringkuk di
bawah rumpun pohon willow yang menyebar
di sepanjang tepi sungai. Pohon-pohon itu
belum pernah ditebang: Yamagata tidak
pernah terancam selama lebih dari enam
belas tahun; pohon willow telah menjadi
simbol kedamaian dan keindahan kota itu. Ia
menunggu dengan cara Tribe dalam waktu
yang lama, melambatkan napas dan detak
jantungnya. Bulan sudah terbenam, kota
sunyi senyap. Akhirnya Takeo mengambil
napas sedalam-dalamnya, lalu menyehnap,
tersembunyi oleh daun-daun willow, masuk
ke sungai, berenang di bawah permukaan
aimya.
Diikutinya jalur yang pernah dilewatinya
hampir separuh hidupnya yang silam, saat itu
tujuannya adalah mengakhiri penderitaan
kaum Hidden yang disiksa. Sudah bertahun-
tahun lamanya sejak para tawanan digantung
di dalam kerangkeng di sini; yang pasti masa-
masa menyedihkan itu takkan kembali?
Namun kala itu ia masih muda, dan saat itu
ia membawa besi pengait untuk menuruni
dinding. Kini, dalam keadaan cacat, terluka,
lelah, ia merasa bak seekor serangga cacat
yang merayap dengan canggung menaiki
bagian depan kastil.
Takeo menyeberangi dinding sebelah luar
yang kedua; di sini juga, para penjaga gugup
dan gelisah, bingung sekaligus gembira
karena bisa menguasai kastil dengan mudah.
Didengarnya perang kecil yang berlangsung
cepat dan dengan pertumpahan darah untuk
merebutnya. Kekagetan mereka diwarnai
dengan kekaguman pada kekejaman Kaede,
kegembiraan mereka atas kebangkitan Klan
Seishuu dengan mengorbankan Klan Otori.
Pemikiran mereka yang plin-plan dan sempit
membangkitkan amarahnya. Sewaktu
memanjat turun memasuki dinding sebelah
luar dan berlari dengan langkah ringan
melewati jalan batu yang sempit ke taman
kediaman, suasana hatinya terasa sengit dan
putus asa.
Dua penjaga lagi duduk di samping
tungku bara kecil di salah satu ujung
beranda, lentera menyala di kedua sisinya.
Takeo melewati mereka begitu dekat hingga
dilihatnya nyala api meliuk dan asapnya
bergulung. Kedua penjaga itu terperanjat,
lalu melihat ke gelapnya taman. Seekor
burung hantu terbang rendah lewat, dan
mereka menertawai ketakutan mereka
sendiri.
"Malam untuk hantu," kata salah sarunya
dengan nada mengejek.
Semua pintu terbuka, cahaya kecil samar-
samar di sudut setiap ruangan. Bisa didengar-
nya napas penghuninya yang sedang tidur.
Aku mengenal napasnya, pikirnya. Dia tidur
di sampingku selama malam-malam kebe-
rsamaan kami.
Takeo mengira sudah menemukan Kaede
tidur di kamar yang besar, tapi saat berlutut
di samping perempuan yang sedang tidur itu,
disadarinya kalau itu Hana. Ia terpana
dengan kebencian yang dirasakannya atas
adik Kaede itu, namun kemudian meninggal-
kannya dan terus berjalan.
Udara terasa pengap di dalam rumah itu:
tubuhnya masih basah karena berenang di
sungai sebelumnya tapi tidak merasa
kedinginan. Ia membungkuk di atas be-
berapa perempuan yang tengah tertidur dan
mendengarkan napas mereka. Tak satu pun
dari mereka adalah Kaede.
Saat itu puncak musim panas, kurang dari
enam minggu dari waktu matahari berada
pada jarak terjauh dari garis khatulistiwa.
Matahari akan segera terbit. Ia tak bisa terus
berada di sini. Satu-satunya tujuannya adalah
menemui Kaede: sekarang ia tidak bisa
menemukannya sehingga tidak tahu apa yang
harus dilakukan. Takeo kembali ke taman;
saat itulah diperhatikannya bentuk samar
bangunan terpisah yang tidak ia lihat
sebelumnya. Berjalan ke arah bangunan itu,
disadarinya kalau itu adalah paviliun yang
dibangun di atas aliran sungai, dan di balik
bunyi air sungai, dikenalinya napas Kaede.
Di sini juga ditaruh lentera yang menyala,
sinarnya sangat redup seolah minyaknya
sudah hampir habis. Kaede duduk bersila,
menatap ke kegelapan. Takeo tidak bisa
melihat wajahnya.
Jantungnya berdetak jauh lebih kencang
dibandingkan dengan saat menghadapi
pertempuran mana pun. Ia membiarkan
dirinya terlihat saat melangkah di lantai
papan, dan berbisik, "Kaede. Ini Takeo."
Tangan Kaede langsung bergerak ke
samping, lalu mengeluarkan sebilah pisau
kecil.
"Aku datang bukan untuk menyakitimu,"
ujarnya. "Bagaimana kau bisa berpikir
begitu?"
"Kau tidak bisa menyakitiku lebih dari
yang sudah kau lakukan," sahut Kaede. "Aku
bisa saja membunuhmu, tapi aku percaya
kalau hanya putramu yang bisa melaku-
kannya!"
Takeo diam membisu, memahami apa
yang telah terjadi.
"Siapa yang mengatakannya?"
"Apa itu penting? Sepertinya semua orang
sudah tahu kecuali aku."
"Itu sudah lama berlalu. Kukira...."
Kaede tidak membiarkan Takeo melanjut-
kan. "Tindakannya mungkin sudah lama
berlalu. Tapi kau menipuku tanpa henti. Kau
membohongiku selama masa-masa kita ber-
sama. Itulah yang tak kumaafkan."
"Aku tidak ingin menyakitimu," ujar
Takeo.
"Bagaimana kau bisa menatap aku
mengandung anakmu, senantiasa ketakutan
kalau aku mungkin mengandung anak laki-
laki yang akan membunuhmu? Sementara
aku merindukan anak laki-laki, kau berdoa
untuk menghindarinya. Kau lebih suka
melihatku dikutuk dengan si kembar, dan
saat putramu lahir kau berharap dia mati.
Bahkan mungkin kau yang mengatur
kematiannya."
"Tidak," sahut Takeo marah, "Aku takkan
membunuh seorang anak pun, apalagi darah
dagingku sendiri." Takeo berusaha bicara
dengan lebih tenang, untuk menyelesaikan
masalah. "Kematiannya adalah kehilangan
besarmembuatmu melakukan semua ini."
"Kejadian itu membuka mataku melihat
siapa sebenarnya dirimu."
Takeo melihat betapa besar amarah dan
kesedihan di hadapannya.
"Satu lagi kebohongan dalam hidup yang
penuh dengan kebohongan," lanjut Kaede.
"Kau tidak membunuh Iida; kau tidak
dibesarkan sebagai ksatria; darahmu ternoda.
Aku telah menyerahkan hidupku pada se-
suatu yang kini kuanggap tak lebih hanya
khayalan."
"Aku tidak pernah berpura-pura padamu,"
sahutnya. "Aku tahu semua kegagalanku;
sudah cukup sering aku membaginya
denganmu."
"Kau pura-pura bersikap terbuka
sementara menyembunyikan banyak rahasia
yang lebih buruk. Apa lagi yang kau rahasia-
kan dariku? Berapa banyak perempuan lain?
Berapa banyak anak laki-laki yang lain?"
"Tidak ada. Aku bersumpah... hanya ada
Muto Yuki, sewaktu aku mengira kau dan
aku telah dipisahkan selamanya."
"Dipisahkan?" ulangnya. "Tidak ada yang
memisahkan kita, kecuali dirimu sendiri. Kau
memilih untuk pergi: meninggalkan diriku,
karena kau tidak ingin mati."
Kata-kata ini sedikit banyak benar adanya
hingga membuatnya merasa sangat malu.
"Kau benar," ujarnya. "Waktu itu aku
memang bodoh dan pengecut. Kumohon
kau memaafkanku. Demi nasib seluruh
negara ini. Kumohon untuk tidak meng-
hancurkan semua yang telah kita bangun
bersama."
Takeo ingin menjelaskan bagaimana
mereka telah menjaga negara ini dalam
keselarasan, bagaimana keseimbangan itu
jangan sampai hilang, namun tidak ada kata-
kata yang memperbaiki semua yang telah
musnah.
"Kaulah yang menghancurkannya," sahut
Kaede. "Aku takkan memaafkanmu. Satu-
satunya yang bisa menghilangkan pen-
deritaanku adalah melihatmu mati." Kaede
menambahkan dengan nada getir, "Satu hal
terhormat yaitu mencabut nyawamu sendiri,
tapi kau bukanlah ksatria dan takkan
melakukannya, kan?"
"Sesuai janjiku padamu, aku takkan
melakukannya," sahut Takeo dengan nada
lirih.
"Aku membebaskanmu dari janji itu. Ini,
ambil pisau ini! Habisi nyawamu, saat itulah
baru aku bisa maafkan!"
Kaede menyodorkan pisau itu ke arah
Takeo, menatap langsung ke wajahnya.
Takeo tak ingin menatapnya, takut istrinya
terkena tatapan Kikuta. Ditatapnya pisau itu,
tergoda untuk menggunakannya, dan
menikam dirinya sendiri. Tak ada rasa sakit
di tubuhnya yang akan terasa lebih sakit
dibandingkan penderitaan yang menusuk
jiwanya.
Takeo berkata, berusaha mengendalikan
diri, mendengarkan kata-katanya yang
terdengar kaku dan formal seakan mereka
tidak saling kenal, "Ada beberapa hal yang
harus diatur terlebih dulu. Masa depan
Shigeko harus dipastikan. Kaisar telah
mengakui dirinya. Baiklah, ada banyak hal
yang ingin kuceritakan padamu, tapi
mungkin aku takkan sempat melakukannya.
Aku siap mengasingkan diri demi masa
depan putri kita: aku yakin kau akan
membuat kesepakatan yang sesuai dengan
Zenko."
"Kau takkan bertarung layaknya ksatria:
kau takkan mati layaknya ksatria. Betapa
hinanya kupandang dirimu di mataku!
Kurasa kini kau akan menyelinap diam-diam,
seperti layaknya penyihir, dan kau memang
seperti itu."
Kaede bangkit, seraya berteriak, "Penjaga!
Tolong! Ada penyusup!"
Gerakannya yang tiba-tiba membuat
lentera padam. Paviliun seketika gelap gulita.
Obor para penjaga bersinar redup di sela-sela
pepohonan. Dari kejauhan Takeo mendengar
ayam jantan berkokok. Kata-kata Kaede
menyengat dirinya seperti pisau belati Kotaro
yang beracun. Ia tak ingin ditemukan di sini
seperti pencuri atau buronan. Tak sanggup
menanggung rasa malu lebih jauh lagi.
Takeo tak pernah begitu kesulitan
menggunakan kemampuan menghilangnya.
Konsentrasinya buyar: merasa seakan dirinya
hancur berkeping-keping. Ia berlari ke
dinding taman lalu memanjat ke atasnya,
menyeberangi pelataran menuju dinding
sebelah luar lalu merayap memanjatnya. Saat
di puncak, bisa dilihatnya ke bawah tempat
permukaan parit berkilauan hitam pekat bak
cairan tinta. Langit semakin pucat di ufuk
timur.
Di belakangnya terdengar derap langkah
kaki. Ia kehilangan kemampuan menghilang,
mendengar keriat-keriut busur panah yang
meregang, desing anak panah, dan setengah
menyelam, setengah terjatuh ke dalam air;
terjun dengan tiba-tiba membuat napasnya
terputus dan telinganya berdengung kencang.
Ia muncul ke permukaan, menghela napas,
melihat anak panah di sebelahnya, men-
dengar kecipak air lain di sekitarnya. Ia
menyelam lagi lalu berenang menuju ke
tepian, menarik dirinya untuk berlindung di
bawah pepohonan willow.
Takeo menghela napas beberapa kali,
mengibaskan air dari tubuh bak seekor
anjing, menghilang lagi lalu berlari melewati
jalan-jalan menuju gerbang kota. Gerbang
telah dibuka, dan orang-orang yang telah
menunggu semalaman untuk meninggalkan
kota, sudah berjalan melewatinya. Harta
benda mereka terbungkus dalam buntalan di
kayu panggul atau dimuat ke dalam kereta
kecil yang ditarik dengan tangan, tatapan
mata anak-anak mereka tampak serius dan
kebingungan.
Takeo merasa amat iba melihat keadaan
mereka, sekali lagi berada di bawah
kekuasaan para bangsawan. Di sela ke-
sedihannya, ia berusaha mencari cara untuk
menolong mereka, namun ia merasa hampa,
yang terpikirkan olehnya hanyalah, semuanya
telah berakhir.
Di dalam benaknya dilihatnya taman di
Terayama dan lukisan-lukisan yang tiada
tandingannya, mendengar kata-kata Matsuda
bergema selama ini. Kembalilah kepada kami
saat semua ini telah berakhir.
Akankah pernah berakhir? Kala itu ia
bertanya.
Semua yang memiliki permulaan pasti ada
akhirnya, sahut Matsuda saat itu.
Kini akhir dari segalanya telah tiba tanpa
bisa dihindari; jaring tipis Surga telah
menjerat dirinya, seakan pada akhirnya
menjerat semua makhluk hidup. Semuanya
telah berakhir. Ia akan kembali ke Terayama.
Ditemukannya Gemba masih duduk
bermeditasi di tepi hutan, kuda tengah
makan rumput di sampingnya, surai mereka
berbintik-bintik dengan butiran embun.
Kedua kuda itu mengangkat kepala dan
meringkik melihat kedatangannya.
Gemba tidak bicara, hanya menatap Takeo
dengan matanya yang cerdas dan penuh
welas asih, kemudian berdiri dan memasang
pelana, senantiasa bersenandung di balik
napasnya. Bahu Takeo terasa sakit lagi dan
dirasakannya demam menyerangnya.
Matahari terbit, menghanguskan kabut
saat mereka berjalan menyusuri jalanan
sempit menuju kuil, jauh di tengah
pegunungan. Ada semacam rasa ringan
menyelimuti dirinya. Segalanya berangsur
sirna di balik irama derap kaki kuda dan
panasnya sinar matahari. Kesedihan,
penyesalan, rasa malu semuanya berbaur
menjadi satu. Diingatnya keadaan seakan
dalam mimpi yang pernah dialaminya saat di
Mino ketika pertama kali berhadapan dengan
kekerasan penuh pertumpahan darah dari
para ksatria. Kini nampak baginya kalau
dirinya memang sudah mati pada saat itu dan
hidupnya sama tidak nyatanya seperti kabut,
mimpi tentang hasrat dan perjuangan yang
terbakar habis bersama cahaya matahari yang
cerah serta menyilaukan.*
Shigeko melakukan perjalanan ke Inuyama
dengan perlahan bersama banyak korban
luka, termasuk kuda ayahnya, Tenba dan
orang yang dicintainya. Kendati sebagian
besar dari mereka dalam kondisi yang parah,
Kahei telah memerintahkan mereka me-
nunggu di dataran sementara pasukan utama
kembali ke Inuyama. Kondisi jalan yang
curam dan sempit, dan keadaan yang sudah
sangat mendesak hingga mereka harus
bergerak cepat. Ketika akhirnya jalan ber-
angsur lebih lebar, Shigeko mengira kalau
kuda itu dan kirin sudah pulih, dan Hiroshi
akan meninggal: di siang hari ia meng-
habiskan waktu untuk merawat mereka yang
terluka bersama Mai. Di malam hari dibiar-
kannya kelemahan dalam dirinya membuat
tawar-menawar yang mustahil, karena Surga
dan para dewa mengabulkan semua yang
mereka inginkan kecuali menyelamatkan
Hiroshi. Luka Shigeko pulih dengan cepat: ia
berjalan selama beberapa hari pertama; tak
masalah kalau ia berjalan terpincang-pincang
karena mereka bergerak secara perlahan
menuruni jalur pegunungan. Korban yang
luka mengigau atau mengoceh karena
demam, dan setiap pagi mereka harus me-
ninggalkan orang yang meninggal di malam
harinya. Betapa mengerikannya kemenangan
dalam perang, pikirnya.
Hiroshi berbaring tanpa mengeluh di
tandu, terombang-ambing antara sadar dan
tidak sadar. Setiap pagi Shigeko berharap
menemukan tubuh pemuda itu kaku dan
dingin, namun meski keadaannya tak
kunjung membaik, Hiroshi belum mati.
Pada hari ketiga, jalanan terasa lebih nyaman,
lerengnya tak lagi terlalu curam dan mereka
mulai melintasi jarak yang lebih jauh antara
matahari terbit hingga matahari terbenam.
Malam itu mereka beristirahat di desa
pertama yang layak disinggahi. Tersedia
seekor sapi jantan dan gerobak, dan Hiroshi
dipindahkan ke atasnya pada keesokan hari-
nya. Shigeko menaiki gerobak itu dan duduk
di sampingnya, membasahi bibirnya dengan
air serta melindungi wajahnya dari sinar
matahari. Tenba dan kirin berjalan ber-
dampingan, keduanya pincang.
Tepat sebelum sampai di Inuyama, mereka
bertemu Tabib Ishida dan iring-iringan kuda
beban. Iring-iringan itu membawa kertas
halus dan kain sutra untuk membalut luka,
begitu pula dengan tanaman obat-obatan dan
salep. Dengan perawatannya, banyak dari
mereka yang terluka bisa sembuh. Meskipun
Ishida tidak menjanjikan apa-apa kepada
Shigeko, dalam diri gadis itu muncul
secercah harapan kalau Hiroshi mungkin
termasuk di antara mereka yang bisa sembuh.
Suasana hati Ishida murung, jelas kalau
pikirannya ada di tempat lain. Saat sedang
tidak sibuk merawat orang sakit, ia suka
berjalan di samping kirin yang jalannya
semakin melambat. Hewan itu nampak jelas
tengah kesakitan: kotorannya hampir seperti
cairan, dan tulang-tulangnya menonjol
seperti benjolan. Namun kirin tetap lembut
seperti biasa, dan kelihatannya senang
ditemani Ishida.
Shigeko mengetahui tentang kematian
adik bungsunya dan ternyata ibunya
kehilangan akal karena sedih; ia ingin sekali
pulang ke Negara Tengah untuk menemani
ayahnya. Juga sangat khawatir dengan si
kembar. Ishida mengatakan pernah bertemu
Miki di Hagi, tapi tidak ada yang tahu di
mana Maya berada. Setelah satu minggu di
Inuyama, Ishida juga mengatakan harus pergi
ke Hofu karena tidak bisa berhenti memikir-
kan istrinya, Shizuka.
Namun mereka juga tidak mendapat kabar
apa-apa, dan tanpa kabar sepertinya akan
menjadi tindakan bodoh mengambil resiko
untuk melanjutkan perjalanan: mereka tidak
tahu siapa yang menguasai Hofu; di mana
Zenko bersama pasukannya berada atau
sudah seberapa jauh Kahei dalam perjalanan
pulang.
Lagipula, kirin tidak bisa berjalan lebih
jauh lagi, begitu pula Hiroshi. Shigeko
kembali kepada keputusannya untuk tetap di
Inuyama sampai mendapat kabar dari
ayahnya. Ia memohon pada Ishida untuk
menemaninya dan membantunya merawat
korban luka dan kirin, dan tabib itu dengan
enggan menyetujui. Shigeko amat berterima
kasih karena keberadaan Ishida sangat berarti
baginya: Shigeko memaksa Ishida untuk
menceritakan semua yang diketahuinya
kepada Minora dan memastikan semua
peristiwa, walaupun buruk, dicatat dengan
baik.
Bulan dari bulan kedelapan berada dalam
bentuk seperempat sewaktu pembawa pesan
akhirnya tiba, tapi baik mereka maupun surat
yang mereka bawa bukanlah yang diharapkan
Shigeko.
Mereka datang naik kapal dari Akashi dan
mengenakan lencana Saga Hideki di jubah,
bersikap penuh hormat dan kerendahan hati
serta meminta berbicara dengan Lady
Maruyama. Shigeko terkejut: terakhir kali
dilihatnya Lord Saga dibuat buta oleh panah-
nya. Jika ia bisa menduga sesuatu datang dari
laki-laki itu, maka tak lain adalah kapal
perang. Untuk pertama kalinya selama ber-
minggu-minggu Shigeko baru menyadari
bagaimana keadaan dirinya. Ia mandi dan
mengeramasi rambut panjangnya, lalu
meminjam jubah indah dari bibinya, Ai,
karena semua benda miliknya sudah
ditinggalkan dalam perjalanan pulang dari
ibukota. Diterimanya para utusan itu di
raang pertemuan kediaman kastil: mereka
membawa banyak hadiah, dan surat yang
ditulis sendiri oleh Saga Hideki.
Shigeko menyambut mereka dengan sikap
anggun, seraya menyembunyikan rasa malu-
nya. "Kurasa Lord Saga sehat-sehat saja,"
tanyanya. Mereka meyakinkan dirinya kalau
Saga sudah pulih dari luka yang dideritanya
akibat perang; mata kirinya buta, tapi selain
itu kesehatannya baik-baik saja.
Shigeko memberi perintah untuk meng-
hibur para utusan itu dengan upacara
semewah mungkin. Kemudian ia meng-
undurkan diri untuk membaca surat Lord
Saga untuknya. Dia pasti mengancam,
pikirnya, atau memberi hukuman yang
setimpal. Namun ternyata isi surat itu agak
berbeda, hangat dan penuh hormat.
Saga menulis bahwa dia sangat menyesali
serangannya atas Lord Otori: merasa bahwa
satu-satunya strategi untuk hasil akhir yang
memuaskan adalah menghapuskan ancaman
dari Arai terhadap Otori; pernikahan antara
dirinya dan Lady Maruyama bisa me-
negaskan hal itu. Bila Shigeko setuju
ditunangkan, maka ia akan segera menyebar
pasukannya untuk bertempur bersama Lord
Ototi beserta komandannya, Miyoshi Kahei.
Saga tak menyebut tentang luka yang
dideritanya: setelah selesai membaca surat
itu, Shigeko merasakan, bersama dengan
keheranan dan marah, sesuatu yang mirip
dengan kekaguman. Disadarinya kalau Saga
berharap mengambil alih kendali atas Tiga
Negara, pertama dengan ancaman, kemudian
dengan dalih, dan terakhir dengan kekerasan.
Laki-laki itu sudah kalah dalam satu
peperangan, namun belum menyerah: justru
sebaliknya; dia menyiapkan serangan lain;
tapi kemudian mengubah taktiknya.
Shigeko kembali ke ruang pertemuan dan
mengatakan kepada para tamunya bahwa dia
akan menulis surat balasan kepada Lord Saga
keesokan harinya. Setelah mereka ber-
istirahat, Shigeko pergi ke ruangan tempat
Hiroshi berbaring di dekat pintu-pintu yang
terbuka, menghadap ke taman. Aroma dan
suara malam musim panas memenuhi udara.
Shigeko berlutut di sampingnya. Hiroshi
terjaga.
"Apakah kau kesakitan?" tanya Shigeko
pelan.
Hiroshi menggeleng pelan sekali, tapi
Shigeko tahu kalau laki-laki itu berbohong;
bisa dilihat betapa kurus badannya, kulitnya
mengencang dan menguning di atas tulang-
nya.
"Ishida bilang kalau aku takkan mati, kali
ini," ujar Hiroshi. "Tapi dia tidak bisa ber-
janji kalau aku bisa menggunakan kedua
kakiku dengan baik lagi. Aku sangsi akan bisa
menunggang kuda lagi, atau berguna dalam
perang."
"Kuharap kita tak perlu lagi berperang
seperti itu," sahut Shigeko. Diraihnya tangan
Hiroshi; meletakkan di dalam genggaman
kedua tangannya. Tangan itu selemah dan
sekering helaian daun di musim gugur. "Kau
masih demam."
"Hanya sedikit. Malam ini terasa panas."
Tiba-tiba air mata mengambang di pelupuk
mata Shigeko.
"Aku takkan mati," kata Hiroshi lagi.
"Jangan menangisi diriku. Aku akan kembali
ke Terayama dan mengabdikan diriku
sepenuhnya pada Ajaran Houou. Aku tak
percaya kalau kita gagal: kita pasti telah
melakukan kesalahan, melupakan sesuatu."
Suaranya kian melemah, dan Shigeko bisa
melihat kalau laki-laki itu sudah pergi ke
dunia lain. Matanya terpejam.
"Hiroshi," serunya ketakutan.
Tangan Hiroshi bergerak lalu meng-
genggam tangan Shigeko. Bisa dirasakannya
tekanan jari pemuda itu; nadinya berdenyut,
lemah namun teratur. Shigeko berkata, tidak
tahu Hiroshi mendengarnya atau tidak,
"Lord Saga menulis surat, menyarankan lagi
kalau sebaiknya aku menikah dengannya."
Hiroshi tersenyum tipis. "Tentu saja kau
akan menikah dengannya."
"Aku belum memutuskan," sahutnya.
Shigeko duduk memegangi tangan Hiroshi
semalaman, sementara pemuda itu ter-
ombang-ambing antara keadaan tidur dan
terjaga. Dari waktu ke waktu mereka
berbincang, tentang kuda dan masa kecil
mereka di Hagi. Shigeko merasa sedang
mengucapkan selamat tinggal pada Hiroshi;
kalau mereka takkan berada sedekat ini lagi.
Mereka berdua bak bintang yang beterbaran
di langit, yang nampak saling berdekatan
namun kemudian berayun terpisahkan oleh
gerakan tak terelakkan dari surga. Sejak
malam itu, lintasan nasib menjauhkan diri
mereka dari satu dengan yang lainnya, meski
mereka berdua tak akan berhenti merasakan
kasih sayang yang tak kasat mata.
***
Seakan menjawab tawar-menawar yang tak
terucapkan dari mulut Shigeko, ternyata
kirin yang mati. Ishida, dengan pikirannya
yang sangat kacau, datang memberi-tahu
Shigeko keesokan sorenya.
"Tadinya sudah lebih baik," tuturnya.
"Kukira hewan itu sudah melewati masa
kritisnya. Tapi kemudian berbaring saat
malam hari lalu tidak bangun lagi. Sungguh
hewan yang malang. Aku berharap tidak
pernah membawa nya kemari."
"Aku harus melihatnya," ujar Shigeko, lalu
pergi bersama Ishida ke istal di sisi mata air
padang rumput, tempat dibangun sebuah
kandang. Shigeko pun merasakan kesedihan
menyelimuti dirinya melihat kematian hewan
yang cantik serta lembut itu. Saat dilihatnya
hewan itu, besar dan terbaring kaku tak
bernyawa, mata dengan bulu mata panjang-
nya tampak suram dan penuh debu. Shigeko
merasakan firasat kuat dengan kejadian ini,
"Inilah akhir dari segalanya," tuturnya
pada Ishida. "Kirin muncul saat penguasa
bersikap adil dan negara penuh damai:
kematiannya berarti semuanya telah sirna."
"Kirin hanyalah hewan biasa," sahut
Ishida. "Luar biasa dan menakjubkan, tapi
bukan berasal dari dongeng."
Kendati demikian, Shigeko tak bisa
menyingkirkan keyakinan kalau ayahnya
sudah tiada.
Disentuhnya kulit lembut kirin yang
masih kelihatan berkilau, dan teringat kata-
kata Saga.
"Dia akan mendapatkan keinginannya,"
katanya dengan lantang. Diperintahkannya
agar hewan itu dikuliti untuk diawetkan. Ia
akan mengirimnya, bersama surat balasannya
kepada Lord Saga.
Shigeko kembali ke penginapan, meminta
dibawakan atat tulis. Ketika pelayan kembali,
Minoru datang bersama mereka. Selama
beberapa hari terakhir Shigeko merasa kalau
Minoru ingin bicara berdua saja dengannya
tapi tak pernah ada kesempatan. Kini
Minoru berlutut di hadapannya dan meng-
haturkan sebuah gulungan kertas.
"Ayahanda Lady Maruyama memerintah-
kan aku untuk menaruh ini di tangan Lady
Maruyama," katanya dengan suara pelan.
Ketika Shigeko mengambilnya, Minoru
membungkuk hormat sampai ke lantai di
hadapannya, orang pertama yang meng-
hormati dirinya sebagai penguasa Tiga
Negara.*
Dari Kubo Makoto, untuk Lady Otori. Aku
ingin menceritakan kepadamu tentang hari-
hari terakhir dalam hidup suamimu.
Kala itu sudah hampir musim gugur di
pegunungan di sini. Malam-malam terasa
dingin. Dua malam yang lalu, aku mendengar
suara burung hantu rajawali di pemakaman,
tapi tadi malam sudah tidak ada. Burung itu
sudah terbang ke selatan. Dedaunan mulai
berganti warna: tak lama lagi kami akan
melihat es pertama, lalu salju.
Takeo datang ke biara kami bersama
Miyoshi Gemba di awal bulan kedelapan; aku
lega melihatnya masih hidup, karena kami
sudah mendengar kehancuran Hagi dan
pasukan Zenko sudah sampai ke Yamagata.
Menurutku jelas terlihat bahwa tidak ada
serangan di Tiga Negara bisa berhasil saat
Takeo masih hidup, dan aku tahu Zenko akan
berusaha membunuhnya sesegera mungkin.
Kala itu waktu tengah hari Takeo dan
Gemba berkuda dari Yamagata. Hari itu
cuaca terasa sangat panas; mereka tidak datang
terburu-buru, tapi lebih dengan cara yang
menyenangkan, seperti peziarah. Jelas sekali
kalau mereka kelelahan, dan Takeo agak
demam... tapi mereka tidak putus asa dan
kelelahan layaknya buronan. Takeo mencerita-
kan tentang pertemuannya denganmu di
malam sebelumnya. Semuanya merupakan
masalah antara suami dan istri, dan orang luar
tidak bisa ikut campur. Yang bisa kukatakan
hanyalah aku sangat menyesal, namun tidak
terkejut. Cinta penuh hasrat tidak bisa hilang
begitu saja, namun berubah menjadi hasrat
yang lain, yaitu kebencian, kecemburuan serta
kekecewaan. Perasaaan yang terjadi antara
laki-laki dan perempuan tidak bisa
diungkapkan dalam satu kata kecuali
berbahaya. Aku sudah jelaskan berulangkali
tentang perasaanku kepada Takeo.
Kemudian kusadari bahwa kejadian kau
diberitahu tentang rahasia itu adalah bagian
dari rencana persekongkolan panjang untuk
mengasingkan Takeo di biara, tempat kami
semua bersumpah untuk tidak membunuh,
serta tidak bersenjata.
Memang, hal pertama yang dilakukan
Takeo yaitu menyingkirkan Jato dari sabuk-
nya.
"Aku datang untuk melukis," tuturnya saat
menyerahkan pedang itu kepadaku. "Kau
pernah merawat pedang ini untukku. Sekarang
aku meninggalkannya di sini sampai putriku,
Shigeko, datang mengambilnya. Pedang ini
diletakkan ke tangan Shigeko oleh Kaisar."
Kemudian dia berkata, "Aku takkan mem-
bunuh lagi. Belum aku begitu gembira seperti
saat ini."
Kami pergi bersama ke makam Lord
Shigeru. Takeo menghabiskan sisa hari itu di
sana. Biasanya banyak peziarah yang datang,
tapi karena ada kabar bahwa perang maka
tempat itu sepi. Setelah itu dia mengatakan
tentang kekhawatirannya kalau rakyatnya
akan mengira dia meninggalkan mereka, tapi
mustahil baginya untuk berperang melawan-
mu. Aku sendiri mengalami pergulatan batin
terbesar yang pernah kualami sejak pertama
kali bersumpah untuk takkan membunuh lagi
Aku tak sanggup melihat kepasrahannya
menerima kematian. Semua perasaaan
manusiawi dalam diriku membuatku ingin
mendesaknya untuk membela diri, untuk
menghancurkan Zenko, dan harus kuakui,
juga menghancurkan dirimu. Aku berjuang
sekuat tenaga mengendalikan semua perasaan
ini siang dan malam.
Takeo sepertinya tidak mengalami per-
gulatan batin dalam dirinya. Malah hampir
kelihatan gembira, meski kutahu ia merasakan
kesedihan yang amat dalam. Bersedih atas
kematian putranya, dan tentu saja, perpisahan
denganmu, namun dia telah menyerahkan
kekuasaan pada Lady Shigeko dan membuang
semua hasratnya. Sedikit demi sedikit
campuran semua perasaan yang diperkuat ini
melampaui kami semua yang ada di biara ini
Semua yang kami lakukan, dari tugas biasa
sehari-hari, sampai ke waktu sakral
melantunkan doa dan meditasi seperti
tersentuh oleh suatu kesadaran yang sangat
mulia.
Takeo mengabdikan dirinya untuk melukis;
mempelajari dan membuat banyak sketsa
burung. Di suatu hari sebelum kematiannya,
dia menyelesaikan panel yang hilang di layar
kasa kami. Kuharap kau bisa melihatnya
kelak. Burung-burung itu kelihatan begitu
hidup hingga mengelabui kucing-kucing di
biara, dan kerap terlihat mengejar mereka.
Setiap hari aku setengah berharap melihat
burung-burung itu sudah terbang.
Takeo juga merasa sangat terhibur dengan
kehadiran putrinya, Miki. Haruka membawa-
nya dari Hagi
"Aku tidak bisa memikirkan tempat lain
yang bisa kami tuju," kata Haruka padaku.
Kami saling mengenal, bertahun-tahun lalu
ketika Takeo berjuang mati-matian setelah
gempa dan pertarungan dengan Kotaro. Aku
sangat menyukainya. Haruka banyak akal dan
pandai, dan kami sangat berterima kasih
kepadanya karena telah membawa Miki
kemari.
Perasaan Miki terguncang dengan semua
peristiwa mengerikan yang disaksikannya,
hingga membuatnya membisu. Ia membuntuti
ayahnya seperti bayangan. Takeo menanyakan
tentang saudara kembarnya, tapi Miki tidak
tahu di mana Maya berada; dia tidak bisa
berbicara dengan ayahnya selain dengan isyarat
tangan.
***
Pada bagian ini Makoto meletakkan kuasnya
sejenak, meregangkan jari-jemarinya dan
menatap keindahan dan ketenangan taman
di luar. Haruskah diceritakannya pada Lady
Otori tentang semua yang Takeo tahu
tentang Maya dan kematian bayi laki-
lakinya? Ataukah membiarkan ke-benaran
tetap menjadi rahasia yang dibawa ke alam
baka? Diambilnya kuas lagi, tinta baru
membuat huruf-hurufnya kelihatan tebal.
***
Di pagi hari kematiannya, Takeo dan Miki
berada di taman. Takeo sudah mulai melukis
sebuah lukisan barulukisan kuda. Gemba
dan aku baru saja keluar untuk bergabung
dengan mereka. Waktu kira-kira menunjukkan
setengah jam dari Waktu Kuda, seperempat
kedua bulan kedelapan, cuaca sangat panas.
Siraman derik jangkrik kedengaran lebih kuat
dari biasanya. Ada dua jalan yang mengarah
ke biara: jalan utama pertama dari
penginapan menuju gerbang biara, dan yang
kedua mengikuti aliran sungai, lebih banyak
ditum-buhi tanaman dan lebih sempit,
mengarah langsung ke taman. Melalui jalan
inilah Kikuta masuk.
Takeo mendengar lebih dulu kedatangan
mereka dibandingkan yang lainnya, dan
sepertinya langsung tahu siapa mereka. Aku
belum pernah bertemu Akio, kendati aku tahu
semua tentang dirinya, dan aku sudah tahu
tentang anak itu selama bertahun-tahun
lamanya, juga tentang ramalan itu. Aku minta
maaf kalau aku mengetahuinya sedang kau
tidak. Andai suamimu menceritakannya
padamu bertahun-tahun yang lalu, tak
diragukan lagi segalanya akan berbeda, namun
dia memilih untuk tidak menceritakannya;
dengan demikian kita membangun nasib kita
sendiri.
Aku melihat dua orang laki-laki berjalan
cepat memasuki taman; di sisi laki-laki yang
lebih muda melompat seekor kucing besar
berbulu hitam, putih dan emas, kucing paling
besar yang pernah kulihat. Sesaat kukira itu
singa. Takeo berkata pelan, "Itu Akio; bawa
Miki pergi." Tak satu pun dari kami bergerak,
kecuali Miki, yang berdiri lalu bergerak men-
dekati ayahnya.
Pemuda itu memegang sepucuk senjata. Aku
mengenali benda itu adalah senjata api, walau
bentuknya jauh lebih kecil dibandingkan
dengan senjata yang digunakan Otori, dan
Akio memegang seperiuk arang yang berasap.
Aku teringat dengan bau asap itu dan
bentuknya yang lurus menjulang di udara yang
tenang.
Takeo menatap pemuda itu. Kusadari kalau
itu adalah putranyasaat itu pertama kalinya
ayah dan anak saling memandang. Mereka
tidak terlalu mirip, namun tetap ada
kemiripannya; warna rambut dan kulit
mereka.
Takeo benar-benar tenang, dan sikapnya
membuat pemuda itu terpakuHisao, begitu
dia dipanggil, walau kurasa kami akan
mengganti namanya. Akio berteriak pada nya.
"Lakukan! Lakukan!" Tapi Hisao seperti
membeku. Perlahan ditaruh tangannya di atas
kepala kucing itu, lalu mendongak seakan ada
orang yang sedang bicara dengannya. Bulu
kudukku berdiri. Aku tidak melihat apa-apa,
tapi Gemba bilang, "Aku bisa merasakan
kehadiran arwah orang mati ada di sini"
Hisao berkata kepada Takeo, "Ibuku bitang
kalau kau adalah ayahku."
Takeo menjawab, "Aku memang ayahmu."
Akio terus berteriak, "Dia bohong. Akulah
ayahmu. Bunuh dia! Bunuh dia!"
Takeo berkata, "Aku memohon agar ibumu
memaafkan aku dan kau juga."
Hisao tertawa tak percaya. "Aku membenci-
mu seumur hidupku!"
Akio memekik, "Dia adalah Si Anjingdia
harus membayar kematian Kikuta Kotaro dan
banyak lagi nyawa dari kalangan Tribe."
Hisao menaikkan senjata api itu. Takeo
bicara dengan jelas, "Jangan coba halangi dia;
jangan sakiti dia."
Tiba-tiba taman dipenuhi dengan burung,
berbulu emas; cahaya matahari menyilaukan,
Hisao menjerit, "Aku tak bisa melakukannya.
Ibu tidak membiarkanku melakukannya,''
Beberapa peristiwa terjadi di waktu
bersamaan. Gemba dan aku berusaha
menyatukan kepingan-kepingannya tapi kami
berdua melihatnya dengan pandangan yang
agak berbeda. Akio merampas senjata api itu
dari Hisao, lalu mendorongnya ke samping.
Kucing itu melompat menyerang Akio,
membenamkan cakarnya di wajah laki-laki
itu. Miki berteriak, "Maya!" Kemudian terjadi
kitatan dan ledakan yang memekakkan telinga,
aroma daging dan bulu yang terbakar.
Senjata itu ternyata salah tembak, dan entah
mengapa meledak. Tangan Akio terbakar, lalu
tak lama kemudian mati kehabisan darah.
Hisao terpaku, dan mengalami luka bakar di
wajahnya, tapi selain itu dia tidak terluka.
Kucing itu sekarat. Miki berlari menghampiri,
menyebut-nyebut nama saudara kembarnya;
aku belum pernah melihat pemandangan yang
begitu mencengangkan: Miki nampak berubah
menjadi sebilah pedang. Cahaya yang terpantul
darinya membutakan mata kami. Gemba dan
aku merasakan kalau ada sesuatu yang ditebas.
Kucing itu berubah wujud saat Miki meng-
hempaskan tubuh menimpanya, dan ketika
kami bisa melihat lagi, Miki tengah memeluk
saudara kembamya yang sudah mati. Kami
percaya kalau ternyata Miki menyelamatkan
Maya dari menjadi roh kucing untuk
selamanya, dan kami berdoa agar kelahiran
kembali Maya terjadi dalam kehidupan yang
lebih baik, tempat orang kembar tidak dibenci
dan ditakuti.
Takeo berlari menghampiri mereka berdua,
lalu memeluk keduanya. Tatapan matanya
bersinar, bak permata. Kemudian dia meng-
hampiri Hisao dan membantunya berdiri lalu
memeluknya, atau yang tadinya kami kira
begitu. Tapi sebenarnya dia sedang mencari-
cari senjata rahasia Tribe di balik pakaian
pemuda itu. Dia menemukan yang dicarinya,
menariknya lalu mencengkeramkan tangan
pemuda itu pada pegangannya. Dia tak ber-
henti menatap pemuda itu selagi mengarahkan
pisaunya ke perutnya sendiri, menyayat dan
memutarnya. Mata Hisao berkaca-kaca dan
ketika Takeo melepaskan tangannya dan mulai
terhuyung-huyung, kaki Hisao juga tertekuk
sewaktu terjatuh terkena tatapan tidur Kikuta.
Takeo jatuh berlutut, di sebelah putranya
yang tertidur.
Kematian tak bisa dicegah akibat dari luka
di perutnya, mengerikan dan menyakitkan.
Aku berkata kepada Gemba, "Ambil Jato," dan
ketika dia kembali membawa Jato, aku
membantu pedang itu melaksakanan tugas
terakhirnya bagi tuannya. Aku takut kalau aku
akan mengecewakannya namun pedang itu
memahami kegunaannya sendiri dan melompat
dari tanganku.
Udara penuh dengan burung memekik
ketakutan, dan bulu emas dan putih
beterbangan ke tanah, menutupi genangan
darah yang mengalir dari tubuhnya.
Itulah terakhir kalinya kami melihat burung
houou. Mereka telah meninggalkan hutan.
Siapa yang tahu kapan mereka akan kembali?
***
Pada bagian ini, dia merasa kesedihan
meliputi dirinya lagi. Sejenak dibiarkannya
perasaan itu menguasai dirinya, meng-
hormati kematian sahabatnya dengan air
mata. Tapi ada satu lagi yang harus ditulis. Ia
mengangkat kuas lagi.
***
Dua dari anak Takeo tinggal bersama kami
Kami akan merawat Hisao di sini. Gemba
percaya bahwa dari kejahatan yang sedemikian
kejinya bisa lahir sebuah jiwa yang besar. Kita
lihat saja nanti. Gemba mengajaknya masuk ke
dalam hutan; anak itu tertarik pada hewan
liar dan pemahaman yang mendalam tentang
mereka. Dia sudah mulai membuat ukiran-
ukiran berbentuk hewan itu, yang kami
anggap sebagai pertanda baik. Kami rasa Miki
membutuhkan kehadiran ibunya bila ingin
memulihkan semua kesedihannya, dan aku
memintamu untuk memanggilnya. Haruka
bisa mengantarnya kepadamu. Dalam diri
Miki sudah terdapat jiwa yang besar, namun
dia sangat rapuh. Dia membutuhkan dirimu.
***
Makoto menatap ke arah taman lagi dan
melihat Miki sedang termangu: dia begitu
kurus hingga mirip hantu. Miki sering meng-
habiskan waktu di sana, tempat ayah dan
saudara kembamya meninggal.
Makoto menggulung suratnya lalu
menaruhnya bersama dengan surat yang
lainnya yang ditulisnya untuk Kaede. Ia
mengulang kisah itu berkali-kali, dengan
banyak selingan. Kadang mengungkapkan
rahasia Maya, kadang menggunakan kata-
kata bijak Takeo tentang perpisahan, untuk
Kaede, untuk dirinya sendiri. Versi surat
yang jujur tanpa hiasan kata-kata ini
dirasakannya hampir mendekati yang
sebenarnya. Kendati demikian, ia tak bisa
mengirimkannya karena tidak tahu di mana
Kaede berada, atau apakah dia masih hidup
atau sudah mati.*
Daun-daun telah berguguran; pepohonan
telah telanjang; burung-burung yang terakhir
bermigrasi telah melintasi langit dalam
barisan panjang bak goresan kuas ketika
Kaede datang ke Terayama saat bulan
purnama dari bulan kesebelas.
Kaede mengajak kedua anak laki-laki,
keponakannya, Sunaomi dan Chikara.
"Aku senang bertemu dengan Sunaomi di
sini," ujar Gemba saat keluar menyambut
mereka. Dia sudah pernah bertemu Sunaomi
tahun lalu, ketika bocah itu melihat burung
houou. "Merupakan keinginan suamimu bila
anak ini ikut dengan kami."
"Mereka tidak tahu lagi harus pergi ke
mana," sahut Kaede. Dia tak ingin berkata
lebih banyak lagi di hadapan mereka berdua.
"Ikutlah bersama Lord Gemba," desaknya
pada mereka. "Lord Gemba akan menunjuk-
kan tempat tinggal kalian."
"Putrimu sedang ke hutan bersama
Haruka untuk mencari jamur." ujar Gemba.
"Putriku ada di sini?" tanya Kaede. Dia
merasa hampir pingsan, lalu bertanya dengan
tersendat-sendat, "Putriku yang mana?"
"Miki," sahut Gemba. "Lady Otori, mari
masuk dan silakan duduk. Kau telah melalui
perjalanan panjang; hari ini cuaca dingin.
Aku akan memanggil Makoto dan dia akan
menceritakan semuanya kepadamu."
Kaede menyadari kalau ia berada di
ambang kehancuran. Selama berminggu-
minggu merasakan kalau dirinya sudah mati
rasa diterpa kesedihan serta keputusasaan. Ia
telah mundur memasuki keadaan dingin
membeku seperti es, seperti yang pernah
dialaminya ketika masih muda dan kesepian.
Di tempat ini segalanya mengingatkan
dirinya pada Takeo dengan ingatan sebening
kaca. Tanpa sadar ia berkhayal kalau Takeo
berada di sini, walau sudah mendengar
tentang kabar kematiannya. Kini dilihatnya
betapa bodohnya khayalan itu: Takeo tidak
ada di sini; dia telah tiada, dan ia takkan
berjumpa lagi dengannya.
Genta biara berdentang, dan Kaede men-
dengar langkah kaki di seberang lantai papan.
Gemba berkata, "Mari ke aula. Aku akan
minta diambilkan tungku bara, juga teh. Kau
tampak kedinginan."
Kebaikan Gemba membuat air matanya
berlinang. Chikara juga mulai terisak.
Sunaomi bicara, berusaha menahan tangis,
"Jangan menangis, adikku. Kita harus ber-
sikap berani."
"Mari," ajak Gemba. "Kami akan ambil-
kan makanan untuk kalian, dan Kepala Biara
kami akan bicara dengan Lady Otori."
Mereka berdiri di lorong biara di pelataran
utama.
Kaede melihat Makoto datang dari arah
yang berlawanan, hampir berlari melintasi
jalan beraspal di sela pepohonan ceri yang
gundul. Kaede tak sanggup melihat ekspresi
di wajah Makoto. Ditutupi wajahnya dengan
lengan bajunya.
Makoto meraih tangan Kaede yang
satunya dan menopang tubuhnya, saat
menuntunnya dengan penuh kelembutan
menuju ke aula tempat lukisan-lukisan
Sesshu disimpan.
"Mari duduk di sini sebentar," ujarnya.
Hembusan napas mereka terlihat putih.
Seorang biarawan datang membawa tungku
bara, dan tak lama setelah itu kembali
membawa teh, namun tak satu pun dari
keduanya meminumnya.
Berusaha untuk bicara, Kaede berkata,
"Aku harus menceritakan tentang kedua
bocah itu kepadamu. Zenko dikepung dan
dikalahkan oleh Saga Hideki dan Miyoshi
Kahei sebulan lalu. Putri sulungku, Shigeko,
ditunangkan dengan Lord Saga. Mereka akan
menikah pada Tahun Baru. Tiga Negara
diambil alih oleh Saga, dan akan disatukan
dengan sisa wilayah Delapan Pulau di bawah
Kaisar. Takeo meninggalkan surat wasiat
yang menyatakan persyaratannya dan Saga
menyetujui semuanya. Shigeko akan
memerintah Tiga Negara dengan derajat
yang sama dengan Saga. Maruyama akan
diwariskan kepada pewaris keturunan
perempuan darinya, dan Saga telah berjanji
takkan ada perubahan dalam cara kami
memerintah."
Sesaat Kaede diam membisu.
"Itu hasil akhir yang baik," ujar Makoto
lembut. "Tujuan Takeo akan tetap diper-
tahankan dan itu berarti berakhirnya
peperangan."
"Zenko dan Hana diperintahkan bunuh
diri," lanjut Kaede. Membicarakan masalah
ini agak membantunya untuk mengendalikan
diri. "Sebelum mati, adikku membunuh
putra bungsunya daripada meninggalkannya.
Tapi aku berhasil membujuk Lord Saga,
melalui putriku, untuk membiarkan
Sunaomi dan Chikara tetap hidup, dengan
syarat mereka dibesarkan di sini. Saga adalah
orang yang kejam dan pragmatis: mereka
akan selamat selama tidak ada orang yang
mencoba memanfaatkan mereka sebagai
pemimpin. Saga akan membunuh mereka
bila melihat ada tanda-tanda akan hal itu.
Tentu saja, mereka akan kehilangan nama
keluarganya: Klan Arai harus dihancurkan.
Orang-orang asing diusir dan agama mereka
dihancurkan. Kurasa kaum Hidden akan
bersembunyi lagi."
Kaede tengah memikirkan Madaren, adik
Takeo. Apa yang akan terjadi padanya?
Apakah Don Joao mengajaknya ikut
bersamanya? Atau malah akan ditinggalkan
lagi?
"Tentu saja kedua anak itu disambut baik
di sini," ujar Makoto. Setelah itu, keduanya
diam membisu.
Akhirnya Kaede angkat bicara, "Lord
Makoto, aku ingin meminta maaf padamu.
Aku selalu merasa tidak suka, bahkan
bersikap tidak ramah padamu, namun kini,
dari semua orang yang ada di dunia ini,
hanya kaulah orang yang kuinginkan untuk
menemaniku. Bolehkah aku juga tinggal di
sini untuk beberapa waktu?"
"Kau dapat tinggal selama yang kau
inginkan. Kehadiranmu bisa menghiburku,"
sahutnya. "Kita berdua mencintainya."
Kaede melihat air mata mengambang di
pelupuk mata Makoto. Lalu Makoto meraih
sesuatu dari belakangnya dan mengeluarkan
segulung kertas dari kotak di lantai, "Aku
berusaha menulis semua yang telah terjadi
dengan sejujur-jujurnya. Bacalah saat kau
sudah merasa mampu melakukannya."
"Aku harus membacanya sekarang," ujar
Kaede, harinya berdebar kencang. "Maukah
kau menemani saat aku membacanya?"
***
Setelah selesai baca, ditaruhnya gulungan
kertas itu dan melihat keluar ke arah taman.
"Dia duduk di sini?"
Makoto mengangguk.
"Dan ini layar kasanya?" Kaede berdiri lalu
melangkah mendekati. Burung-burung gereja
itu menatapnya dengan sinar mata yang
bercahaya. Diulurkan tangannya untuk
menyentuh permukaan lukisan itu.
"Aku tak bisa hidup tanpa dirinya," tiba-
tiba Kaede bicara. "Diriku dipenuhi rasa ber-
salah dan menyesal. Aku mengusirnya hingga
jatuh ke tangan para pembunuhnya. Aku
takkan sanggup memaafkan diriku."
"Tak seorang pun dapat menghindari
nasib," bisik Makoto. Kepala biara itu berdiri
dan menghampiri Kaede hingga mereka
saling berhadapan. "Aku juga merasa tak
akan bisa terlepas dari kesedihanku, tapi aku
berusaha dan menghibur diri dengan
mengetahui bahwa Takeo mati dengan cara
yang sama ketika dia hidup: tanpa rasa takut
dan tetap welas asih. Dia menerima kalau
waktunya telah tiba, dan meninggal dengan
penuh ketenangan. Dimakamkan seperti
keinginannya, di samping makam Shigeru.
Dan seperti Shigeru, dia tidak akan
terlupakan. Terlebih lagi, dia meninggalkan
anak-anaknya, dua putri dan seorang putra."
Kaede berpikir, aku tak siap untuk
menerima kehadiran putranya. Akankah aku
siap menerimanya? Dalam hatiku, yang bisa
kurasakan hanyalah kebencian kepadanya dan
kecemburuan pada ibunya. Sekarang Takeo
berada bersama Yuki. Akankah mereka
bersama dalam semua kehidupan masa datang
mereka, akankah aku bisa berjumpa lagi
dengannya? Apakah jiwa kami akan
terpisahkan untuk selamanya?
"Putranya mengatakan bahwa para arwah
kini sudah beristirahat dengan tenang,"
lanjut Makoto. "Arwah ibunya telah meng-
hantui seumur hidupnya, tapi kini dia telah
terbebas darinya. Kami rasa dia adalah
seorang shaman. Bila penyimpangan dalam
dirinya bisa diluruskan, maka dia bisa men-
jadi sumber kearifan dan karunia."
"Maukah kau tunjukkan tempat suamiku
meninggal?" bisik Kaede.
Makoto mengangguk dan melangkah
keluar ke beranda. Kaede memakai sandal.
Sinar matahari kian meredup; taman
kehilangan semua warnanya, tapi di atas
batu-batu tempat Takeo meninggal ada
percikan darah, mengering hingga berwarna
kecoklatan. Kaede membayangkan kejadian-
nya, tangan Takeo memegang pisau itu,
bilahnya menembus tubuhnya, darah ter-
pancar dari tubuhnya.
Kaede terpuruk di atas tanah, menangis
hingga tubuhnya terguncang.
Aku akan melakukan hal yang sama,
pikirnya. Aku tak tahan menanggung beban
derita ini.
Diraba pisau miliknya, pisau yang selalu
ada di balik jubahnya. Sudah berapa kali ia
berencana mencabut nyawanya sendiri? Di
Inuyama, di rumahnya di Shirakawa,
kemudian berjanji kepada Takeo untuk tidak
menghabisi nyawanya sendiri sampai Takeo
mati lebih dulu. Diingatnya dengan hati
pedih kata-kata yang ia ucapkan pada Takeo.
Ia memaksa suaminya untuk menghabisi
nyawanya sendiri, dan dia telah melakukan-
nya. Kini ia akan melakukan hal yang sama.
Dirasakannya sebersit kebahagiaan. Jiwa dan
raganya akan mengikuti suaminya.
Aku harus melakukan dengan cepat,
pikirnya. Jangan sampai Makoto menghalangi.
Tapi bukan Makoto yang membuat pisau
itu terjatuh dari tangannya; tapi teriakan
seorang gadis dari aula yang mencegahnya,
"Ibu!"
Miki berlari ke taman, telanjang kaki,
rambutnya tergerai. "Ibu! Ibu sudah datang!"
Kaede melihat dengan terkejut betapa saat
ini Miki sangat mirip Takeo, lalu melihat
dirinya sendiri dalam diri putrinya, di usia
itu, di ambang kedewasaan. Dulu ia adalah
sandera, sendirian dan tidak terlindung:
sepanjang masa remajanya, ibunya tidak
berada di sampingnya. Dilihatnya kesedihan
Miki dan berpikir, Aku tidak bisa menambah
kesedihannya. Teringat olehnya kalau Miki
telah kehilangan saudara kembarnya dan air
matanya berlinang lagi menangisi Maya,
menangisi anaknya. Aku harus hidup demi
Miki, dan demi Sunaomi juga Chikara. Dan
tentu saja, demi Shigeko, dan bahkan demi
Hisao, atau apa pun namanya: demi semua
anak Takeo, demi semua anak kami.
Diangkatnya pisau itu lalu dilempamya
jauh-jauh, kemudian membentangkan kedua
tangannya untuk memeluk putrinya.
Sekawanan burung gereja hinggap di
bebatuan dan rerumputan di sekiiar mereka,
memenuhi udara dengan kicauannya.
Kemudian seolah ada sinyal dari kejauhan,
burung-burung itu naik bersamaan lalu
terbang jauh memasuki hutan. ***
TAMAT
UCAPAN TKRIMA KASIH
Saya ingin berterima kasih kepada:
Asialink atas beasiswa yang memungkinkan
saya pergi ke Jepang selama dua belas minggu
di tahun 1999-2000; Australian Council dan
Department Luar Negeri dan Perdagangan
yang telah mendukung program Asialink;
Kedutaan Besar Australia di Tokyo;
Akiyoshidai International Arts Village,
Yamaguchi Prefecture, yang telah
mensponsori saya selama masa tersebut;
ArtsSA, the South Australian Department for
the Arts, yang telah memberi kesempatan
saya untuk menulis; Urinko Gekidan di
Nagoya karena telah mengajak saya untuk
bekerja dengan mereka di tahun 2003.
Suami dan anak-anak saya yang telah
menyokong dan menyemangati saya dengan
berbagai cara,
Di Jepang, Kimura Miyo, Mogi Masaru,
Mogi Akiko, Tokuriki Masako, Tokuriki
Miki, Santo Yuko, Mark Brachmann,
Maxine McArthur, Kori Manami,
Yamaguchi Hiroi, Hosokawa Fumimasa,
Imahori Goro, Imahori Yoko, dan orang-
orang lainnya yang telah membantu dengan
riset dan memandu.
Christopher E. West dan Forest W. Seal
dari situs www.samurai-archieves.com.
Semua penerbit dan agen yang kini
menjadi bagian dari dunia Otori, terutama
Jenny Fading, Donica Bettanin, Sarah
Lutyens dan Joe Regal.
Untuk editorku Bernadette Foley
(Hachette Livre) dan Harriet Wilson (Pan
Macmillan), dan Christine Baker dari
Gallimard.
Sugiyama Kazuko, sang kaligrafi yang
meninggal di tahun 2006.*
Tetralogi Kisah Klan Otori
1. Across The Nightingale Floor
2. Grass For His Pillow
3. Brilliance Of The Moon
4. The Harsh Cry Of The Heron
Ebook (PDF) by
syauqy_arr@yahoo.co.id
Weblog, http://hanaoki.wordpress.com
Anda mungkin juga menyukai
- Kisah Klan Otori IVDokumen624 halamanKisah Klan Otori IVsaffaria100% (2)
- Taiko Leng KapDokumen2.255 halamanTaiko Leng KapIskandar ZulkarnaenBelum ada peringkat
- SenopatiPamungkasBuku I DewiKZ TMTDokumen1.165 halamanSenopatiPamungkasBuku I DewiKZ TMTEdi Sandjaya100% (1)
- Pendekar Pemanah RajawaliDokumen2.443 halamanPendekar Pemanah RajawaliIrwin Iwin WinBelum ada peringkat
- Peristiwa Mei 1998Dokumen157 halamanPeristiwa Mei 1998Sisbo ResnickBelum ada peringkat
- Kang Zusi Website Http://Cerita-silat - Co.ccDokumen288 halamanKang Zusi Website Http://Cerita-silat - Co.ccenthog_146133100% (1)
- Shugyosa 2 PDFDokumen86 halamanShugyosa 2 PDF'Aendy Ngantung'Belum ada peringkat
- SumpahPalapa DewiKZ TMT PDFDokumen1.864 halamanSumpahPalapa DewiKZ TMT PDFYudirwan Tanjung78% (9)
- Badai Laut SelatanDokumen1.287 halamanBadai Laut SelatanSarah Ayu RahmaningrumBelum ada peringkat
- Sin Po 7 April 1932Dokumen28 halamanSin Po 7 April 1932Jimmy Al-AnwarBelum ada peringkat
- Samurai, Jembatan Musim Gugur - Takashi Matsuoka PDFDokumen606 halamanSamurai, Jembatan Musim Gugur - Takashi Matsuoka PDFNuri FauziyahBelum ada peringkat
- Pedang Inti Es - TamatDokumen373 halamanPedang Inti Es - TamattanpausingBelum ada peringkat
- Princess MasakoDokumen372 halamanPrincess MasakoJihan DzakyBelum ada peringkat
- BIOGRAFI DARIPADA SOEHARTO-terkunciDokumen215 halamanBIOGRAFI DARIPADA SOEHARTO-terkunciHendraBelum ada peringkat
- Kisah para Penggetar Langit IDokumen27 halamanKisah para Penggetar Langit IRisangOntosoro100% (1)
- 01 La Galigo IDokumen540 halaman01 La Galigo IAndi Aswin ARBelum ada peringkat
- 07.boneka Hidup BeraksiDokumen144 halaman07.boneka Hidup Beraksiker4sakt1Belum ada peringkat
- Batara - Pedang 3 DimensiDokumen786 halamanBatara - Pedang 3 DimensiDicky Wizanajani r100% (2)
- Masturbasi ReligiusDokumen145 halamanMasturbasi Religiusm azmi shahBelum ada peringkat
- Kisah Klan Otori II, Grass For The PillowDokumen251 halamanKisah Klan Otori II, Grass For The PillowarufizaraBelum ada peringkat
- Pendekar Mabuk - 20. Ladang Pertarungan PDFDokumen138 halamanPendekar Mabuk - 20. Ladang Pertarungan PDFASri WahyuniBelum ada peringkat
- Animorphs 02 - Aksi PenyelamatanDokumen132 halamanAnimorphs 02 - Aksi PenyelamatanrakhmaBelum ada peringkat
- Srikandi Belajar MemanahDokumen185 halamanSrikandi Belajar MemanahluvenaBelum ada peringkat
- Senopati Pamungkas (Tamat)Dokumen1.638 halamanSenopati Pamungkas (Tamat)bankroma100% (2)
- KPH-Pecut Sakti Bajrakirana PDFDokumen472 halamanKPH-Pecut Sakti Bajrakirana PDFYusuf BachtiarBelum ada peringkat
- API Di Bukit Menoreh 1Dokumen493 halamanAPI Di Bukit Menoreh 1Mohamad Rizal Firmansjah100% (1)
- Keluarga Flood Tetangga MenyebalkanDokumen200 halamanKeluarga Flood Tetangga MenyebalkanaiiuwahyuniBelum ada peringkat
- Cahaya Malam (Ikatan Darah Buku 2): Ikatan Darah Buku 2Dari EverandCahaya Malam (Ikatan Darah Buku 2): Ikatan Darah Buku 2Belum ada peringkat
- Kisah 47 RoninDokumen191 halamanKisah 47 Roninhelmy surachmanBelum ada peringkat
- Pendekar Mabuk - 80. Pusaka Jarum Surga PDFDokumen103 halamanPendekar Mabuk - 80. Pusaka Jarum Surga PDFASri Wahyuni100% (1)
- (RBE) Laksmi P - AmbaDokumen569 halaman(RBE) Laksmi P - AmbaallesandroBelum ada peringkat
- The Heike StoryDokumen865 halamanThe Heike StoryRenald Wahyudi BudimanBelum ada peringkat
- Orang-Orang Sisilia PDFDokumen303 halamanOrang-Orang Sisilia PDFAlfian Syahbari Pratama67% (3)
- Kho Ping Hoo - JakalolaDokumen352 halamanKho Ping Hoo - JakalolaAgnesia DamanikBelum ada peringkat
- Link Cerita SilatDokumen12 halamanLink Cerita Silattiraikasih0% (1)
- Mimi Lan MintunaDokumen301 halamanMimi Lan MintunaNaila100% (2)
- Digha Nikaya - Patika Sutta (DN.24) - CDokumen90 halamanDigha Nikaya - Patika Sutta (DN.24) - CpempekplgBelum ada peringkat
- Marketing MuhammadDokumen160 halamanMarketing Muhammadjunio27Belum ada peringkat
- Final New Edition Agar Konsumen Jatuh CintaDokumen176 halamanFinal New Edition Agar Konsumen Jatuh Cintanada sumbang comBelum ada peringkat
- Ramalan Jayabaya Kumpulan PDFDokumen38 halamanRamalan Jayabaya Kumpulan PDFTwee Gezichten SycophantBelum ada peringkat
- Petualangan Detektif SekaratDokumen35 halamanPetualangan Detektif Sekaratjery sokoyBelum ada peringkat
- Buku 3 - Kembalinya San RajaDokumen524 halamanBuku 3 - Kembalinya San RajaNur Anisa Labonu100% (2)
- Kisah Klan Otori IVDokumen329 halamanKisah Klan Otori IVTika SieBelum ada peringkat
- (Isekaipantsu) (DragoIsekai) Arifureta - Volume 03Dokumen312 halaman(Isekaipantsu) (DragoIsekai) Arifureta - Volume 03isekaipantsu100% (1)
- Gaara HidenDokumen277 halamanGaara HidenTakumi FujiwaraBelum ada peringkat
- Eiji Yoshikawa - Musashi 2 WaterDokumen128 halamanEiji Yoshikawa - Musashi 2 WateraerapianginBelum ada peringkat
- Kelas Elit Tahun Kedua Vol 7 CH 1.3Dokumen14 halamanKelas Elit Tahun Kedua Vol 7 CH 1.3Putra WibawaBelum ada peringkat
- 君の名はDokumen6 halaman君の名はHILAL ABDURRAHMANBelum ada peringkat
- Sejarah Hitam Klan UchihaDokumen3 halamanSejarah Hitam Klan UchihaPieter Karunia DeoBelum ada peringkat
- Jmk417e Novel Where Shall We Go This SummerDokumen13 halamanJmk417e Novel Where Shall We Go This SummerNor Azlina NordinBelum ada peringkat
- trIaL hAhAhADokumen4 halamantrIaL hAhAhASri DamayantiBelum ada peringkat
- Analisis NovelDokumen10 halamanAnalisis NovelMelandria NingtyasBelum ada peringkat