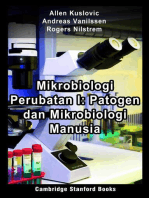BAB III-TINJAUAN PUSTAKA - DBD Anak
BAB III-TINJAUAN PUSTAKA - DBD Anak
Diunggah oleh
Hanarisha Putri AzkiaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
BAB III-TINJAUAN PUSTAKA - DBD Anak
BAB III-TINJAUAN PUSTAKA - DBD Anak
Diunggah oleh
Hanarisha Putri AzkiaHak Cipta:
Format Tersedia
17
BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
I. INFEKSI VIRUS DENGUE
A. Definisi
Demam dengue ( DD ) dan Demam berdarah dengue ( DBD ) merupakan
penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus denguegolongan flavivirus
diprantarai oleh nyamuk aedes aegipty, ditandaidengan demam, nyeri otot
dan / atau nyeri sendi yang disertai dengan leukopenia, ruam kulit,
limfadenopati, trombositopenia dan diathesis hemoragik.
Pada DBD terjadi perembesan plasma yang ditandai oleh hemokonsentrasi
(peningkatan hematokrit) atau penumpukan cairan di rongga tubuh.
Sindrom renjatan dengue (dengue shock syndrome) adalah demam
berdarah dengue yang ditandai oleh renjatan/syok. (Suhendro, 2006).
Infeksi virus dengue pada manusia mengakibatkan spectrum manifestasi
klinis yang bervariasi, antara penyakit paling ringan (mild undifferentiated
febrile illness), demam dengue, demam berdarah dengue sampai demam
berdarah dengue disertai syok (dengue shock syndrome = DSS).
18
Gambar 1. Skema kriteria diagnosis infeksi dengue menurut WHO 2011.
B. Epidemiologi
Demam Berdarah Dengue (DBD) banyak ditemukan di daerah tropis dan
sub-tropis. Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan
pertama dalam jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Sementara itu,
terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health Organization
(WHO) mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD
tertinggi di Asia Tenggara.
Sampai saat ini DBD telah ditemukan di seluruh provinsi di
Indonesia.Pola berjangkitnya infeksi virus dengue dipengaruhi iklim dan
kelembaban udara. Pada suhu yang panas dan kelembaban tinggi (28
32C) nyamuk Aedes dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama. Di
pulau Jawa umumnya infeksi virus dengue dimulai dari bulan Januari dan
meningkat sampai sekitar bulan April Mei tiap tahun(Depkes, 2005).
19
C. Etiologi
Virus dengue termasuk kelompok B Arthropod Borne Virus (Arboviruses)
yang sekarang dikenal sebagai genus flavivirus, famili Flaviviridae.
Bedasarkan genom yang dimiliki, virus dengue termasuk virus (positive
sense single stranded) RNA. Genom ini dapat ditranslasikan langsung
menghasilkan satu rantai polipeptida berupa tiga protein struktural
( capsid, pre-membrane, envelope )dan tujuh protein non struktural (NS1,
NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, dan NS5). Berdasarkan sifat antigen
dikenal ada empat serotipe virus dengue, yaitu: DEN-1, DEN2, DEN-3,
DEN-4. Infeksi salah satu serotipe akan menimbulkan antibodi terhadap
serotipe yang bersangkutan, sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap
serotipe
lain
sangat
kurang,
sehingga
tidak
dapat
memberikan
perlindungan yang memadai terhadap serotipe lain tersebut.
D. Patofisiologi dan Patogenesis
Virus merupakan mikrooganisme yang hanya dapat hidup di dalam sel
hidup. Maka demi kelangsungan hidupnya, virus harus bersaing dengan
sel manusia sebagai pejamu (host) terutama dalam mencukupi kebutuhan
akan protein. Persaingan tersebut sangat tergantung pada daya tahan
pejamu, bila daya tahan baik maka akan terjadi penyembuhan dan timbul
antibodi, namun bila daya tahan rendah maka perjalanan penyakit menjadi
makin berat dan bahkan dapat menimbulkan kematian.
Patogenesis DBD dan SSD (Sindrom Syok Dengue) masih merupakan
masalah yang kontroversial. Dua teori yang banyak dianut pada DBD dan
SSD adalah hipotesis infeksi sekunder (teori secondary heterologous
infection) atau hipotesis immune enhancement. Hipotesis ini menyatakan
secara tidak langsung bahwa pasien yang mengalami infeksi yang kedua
kalinya dengan serotipe virus dengue yang heterolog mempunyai risiko
berat yang lebih besar untuk menderita DBD/Berat. Antibodi heterolog
yang telah ada sebelumnya akan mengenai virus lain yang akan
20
menginfeksi dan kemudian membentuk kompleks antigen antibodi yang
kemudian berikatan dengan Fc reseptor dari membran sel leukosit
terutama makrofag. Oleh karena antibodi heterolog maka virus tidak
dinetralisasikan oleh tubuh sehingga akan bebas melakukan replikasi
dalam sel makrofag. Dihipotesiskan juga mengenai antibody dependent
enhancement (ADE), suatu proses yang akan meningkatkan infeksi dan
replikasi virus dengue di dalam sel mononuklear. Sebagai tanggapan
terhadap infeksi tersebut, terjadi sekresi mediator vasoaktif yang kemudian
menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, sehingga
mengakibatkan keadaan hipovolemia dan syok.
Sebagai akibat infeksi sekunder oleh tipe virus dengue yang berlainan
pada seorang pasien, respons antibodi anamnestik yang akan terjadi dalam
waktu beberapa hari mengakibatkan proliferasi dan transformasi limfosit
dengan menghasilkan titer tinggi antibodi IgG anti dengue. Disamping itu,
replikasi virus dengue terjadi juga dalam limfosit yang bertransformasi
dengan akibat terdapatnya virus dalam jumlah banyak. Hal ini akan
mengakibatkan terbentuknya virus kompleks antigen-antibodi (virus
antibody complex) yang selanjutnya akan mengakibatkan aktivasi sistem
komplemen.
Pelepasan C3a dan C5a akibat aktivasi C3 dan C5 menyebabkan
peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah dan merembesnya
plasma dari ruang intravaskular ke ruang ekstravaskular.Pada pasien
dengan syok berat, volume plasma dapat berkurang sampai lebih dari 30 %
dan berlangsung selama 24-48 jam. Perembesan plasma ini terbukti
dengan adanya, peningkatan kadar hematokrit, penurunan kadar natrium,
dan terdapatnya cairan di dalam rongga serosa (efusi pleura, asites). Syok
yang tidak ditanggulangi secara adekuat, akan menyebabkan asidosis dan
anoksia, yang dapat berakhir fatal; oleh karena itu, pengobatan syok sangat
penting guna mencegah kematian.
21
Gambar 1. Patogenesis Demam Berdarah Dengue.
Sebagai tanggapan terhadap infeksi virus dengue, kompleks antigenantibodi selain mengaktivasi sistem komplemen, juga menyebabkan
agregasi trombosit dan mengaktivitasi sistem koagulasi melalui kerusakan
sel endotel pembuluh darah. Kedua faktor tersebut akan menyebabkan
perdarahan pada DBD. Agregasi trombosit terjadi sebagai akibat dari
perlekatan
kompleks
antigen-antibodi
pada
membran
trombosit
mengakibatkan pengeluaran ADP (adenosin di phosphat), sehingga
trombosit melekat satu sama iain. Hal ini akan menyebabkan trombosit
dihancurkan oleh RES (reticulo endothelial system) sehingga terjadi
trombositopenia. Agregasi trombosit ini akan menyebabkan pengeluaran
platelet faktor III mengakibatkan terjadinya koagulopati konsumtif (KID =
koagulasi intravaskular deseminata), ditandai dengan peningkatan FDP
22
(fibrinogen degredation product) sehingga terjadi penurunan faktor
pembekuan.
Gambar 2. Patogenesis Perdarahan pada DBD2
Agregasi trombosit ini juga mengakibatkan gangguan fungsi trombosit,
sehingga walaupun jumlah trombosit masih cukup banyak, tidak berfungsi
baik. Di sisi lain, aktivasi koagulasi akan menyebabkan aktivasi faktor
Hageman sehingga terjadi aktivasi sistem kinin sehingga memacu
peningkatan permeabilitas kapiler yang dapat mempercepat terjadinya
syok. Jadi, perdarahan masif pada DBD diakibatkan oleh trombositpenia,
penurunan faktor pembekuan (akibat KID), kelainan fungsi trombosit,
dankerusakan dinding endotel kapiler. Akhirnya, perdarahan akan
memperberat syok yang terjadi.
Gigitan nyamuk Aedes menyebabkan infeksi di sel langerhans di
epidermis dan keratinosit. Kemudian menginfeksi sel-sel lainnya seperti
monosit, sel dendritik, makrofrag, sel endotelial dan hepatosit. Monosit
dan
sel
dendritik
yang
terinfeksi
memproduksi
banyak
sitokin
proinflammatori dan kemokin yang selanjutnya mengaktivasi sel T yang
23
diperkirakan menyebabkan disfungsi endotelial. Disfungsi endotelial
menyebabkan peningkatkan permeabilitas pembuluh yang kemudian
menyebabkan perembesan cairan di pleura, rongga peritonium, dan syok.
Sel endotelial juga dirangsang untuk menimbulkan respons imun yang
mengakibatkan permeabilitas vaskular meningkat (Malavige & Ogg,
2012). Menurut IDAI (2012), patogenesis DHF belum jelas namun
terdapat hipotesis yang mendukung seperti heterologous infection
hypothesis atau the sequential infection hypothesis yang menyatakan
bahwa DBD dapat terjadi apabila seseorang setelah terinfeksi virus dengue
pertama kali mendapatkan infeksi kedua dengan virus dengue serotipe lain
dalam jarak waktu 6 bulan sampai 5 tahun (IDAI, 2012). Banyak para ahli
sependapat bahwa infeksi sekunder adalah penyebab beratnya manifestasi
klinis pada penderita DBD (Ginting, 2004).
E. Perjalanan Penyakit Infeksi Dengue
Dalam perjalanan penyakit infeksi dengue, terdapat tiga fase perjalanan
infeksi dengue, yaitu:
1.
Fase
Demam,
ditandai
dengan
dengan
demam
tinggi 2-7
hari
(>38,3 C), kadang dapat disertai kejang demam. Timbul facial flush,
muntah, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tenggorok dengan
faring hiperemis, nyeri hipokondrium kanan dan nyeri perut. Pada
pemeriksaan fisik sering didapatkan manifestasi perdarahan: uji
torniquet positif, petekiae, epistaksis, perdarahan gusi, perdarahan
24
saluran cerna, hematuria (jarang) dan peningkatan darah menstruasi
pada anak perempuan. Hepatomegali sering teraba jelas 2-4 cm
dibawah arcus costae kanan. Peningkatan SGOT dan SGPT menandai
gangguan faal hati.
2. Fase Kritis
Fase kritis terjadi pada saat perembesan plasma yang berawal pada
masa transisi dari saat demam ke bebas demam pada hari ke 3-7
(disebut fase time of fever defervescence) ditandai dengan :
Muntah terus menerus, nyeri perut hebat, hepatomegali
Peningkatan hematokrit 10%-20% di atas nilai dasar
Tanda perembesan plasma seperti efusi pleura dan asites, edema
pada dinding kandung empedu. Foto dada (dengan posisi right
lateral decubitus = RLD) dan ultrasonografi dapat mendeteksi
perembesan plasma tersebut.
Terjadi penurunan kadar albumin >0.5g/dL dari nilai dasar / <3.5 g
% yang merupakan bukti tidak langsung dari tanda perembesan
plasma .
Tanda-tanda syok: anak gelisah sampai terjadi penurunan
kesadaran, sianosis, nafas cepat, nadi teraba lembut sampai tidak
teraba. Hipotensi, tekanan nadi 20 mmHg, dengan peningkatan
tekanan diastolik. Akral dingin, capillary refill time memanjang
(>3 detik). Diuresis menurun (< 1ml/kg berat badan/jam), sampai
anuria.
Komplikasi
berupa
asidosis
metabolik,
hipoksia,
ketidakseimbangan elektrolit, kegagalan multipel organ, dan
perdarahan hebat apabila syok tidak dapat segera diatasi.
3. Fase Penyembuhan, ditandai dengan diuresis membaik dan nafsu
makan
kembali.
Dua
tanda
tersebut
adalah
indikasi
untuk
menghentikan infus, dan dapat dipertimbangkan untuk KRS. Kulit
memerah (Confluent petechial rash) dapat terjadi pada fase ini.
4. Expanded Dengue Syndrome, ditambahkan dalam pedoman terbaru
untuk mengakomodasi kondisi pasien dengan manifestasi klinis yang
berat. Manifestasi tersebut meliputi kelainan hati, ginjal, otak dan
jantung. Kelainan tersebut dapat terjadi karena adanya infeksi penyerta
25
atau komplikasi syok yang berkepanjangan. (UKK infeksi dan
Penyakit Tropis IDAI, 2014).
F. Manifestasi Klinis dan Kriteria Diagnosis Infeksi Dengue
Kriteria diagnosis infeksi dengue dibagi menjadi kriteria diagnosis klinis
dan kriteria diagnosis laboratoris. Kriteria diagnosis klinis penting dalam
penapisan kasus, tatalaksana kasus, memperkirakan prognosis kasus, dan
surveilans. Kriteria diagnosis laboratoris adalah kriteria dengan konfirmasi
laboratorium yang penting dalam laporan, surveilans, dan tindakan
preventif dan promotif.
1. Kriteria Diagnosis Klinis
Manifestasi klinis infeksi dengue sangat bervariasi dan sulit dibedakan
dari penyakit infeksi lain, terutama pada fase awal perjalanan penyakit.
Sehingga dibagi menjadi beberapa kriteria, antara lain :
a. Kriteria Klinis Demam Dengue
Demam 2-7 hari timbul mendadak, tinggi, terus menerus,
bifasik.
Manifestasi perdarahan baik spontan seperti, ptekie, purpura,
ekimosis, epitaksis, perdarahan gusi, hemetesis, dan atau
melena; maupun berupa uji torniquet positif.
Nyeri kepala, mialgia, artalgia, nyeri retro-orbital
Dijumpai kasus DBD di lingkungan sekolah dan sekitaran
rumah.
Leukopenia <4000/mm3
Trombositopenia <100.000/mm3
Apabila ditemukan gejala demam ditambah dengan adanya dua
atau lebih tanda dan gejala lain, diagnosis klinis demam dengue
dapat ditegakkan.
b. Demam Berdarah Dengue
Demam 2-7 hari yang timbul mendadak, tinggi, terus-menerus,
bifasik
Manifestasi perdarahan baik spontan seperti petekie, purpura,
ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis dan atau
26
melena, hematuri (jarang); maupun uji torniquet positif,
dijumpai facial flush
Nyeri kepala, mialgia, artralgia, nyeri retro-orbital, nyeri
tenggorokan dengan faring hiperemis
Dijumpai kasus DBD di lingkungan sekolah dan disekitar
rumah
Hepatomegali
Terdapat kebocoran plasma yang ditandai dengan salah satu
tanda/gejala:
-
Peningkatan nilai hematokrit > 20% dari pemeriksaan
awalatau dari data populasi menurut umur
- Ditemukan adanya efusi pleura, asites
- Hipoalbuminemia, hipoproteinemia
Trombositopenia < 100.000/mm3
Demam disertai dengan 2 atau lebih manifestasi klinis, ditambah
bukti perembesan plasma dan trombositopeni cukup untuk
menegakkan diagnosis DBD.
c. Tanda bahaya untuk mengantisipasi terjadi syok pada pasien DBD:
Demam turun tetapi keadaan anak memburuk
Nyeri perut dan nyeri tekan abdomen
Muntah yang menetap
Letargi, gelisah
Perdarahan mukosa
Hepatomegali
Akumulasi cairan
Oligouria
Peningkatan kadar hematokrit bersamaan dengan penurunan
cepat jumlah trombosit
Hematokrit awal yang tinggi
(UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, 2014)
2. Kriteria Diagnosis Laboratorium
a. Probable dengue, apabila diagnosis klinis diperkuat oleh hasil
pemeriksaan serologi anti dengue
27
b. Confirmed dengue, apabila diagnosis klinis diperkuat dengan
deteksi genom virus dengue dengan pemeriksaan RT PCR, antigen
dengue NS1, atau apabila didapatkan serokonversi pemeriksaan
IgG dan IgM (dari negatif menjadi positif) pada pemeriksaan
serologi berpasangan.
Pemeriksaan penunjang Laboratorium
1. Pemeriksaan darah perifer, yaitu hemoglobin, leukosit, hitung
jenis, hematokrit, dan trombosit.
2. Antigen NS1 dapat dideteksi pada hari ke-1 setelah demam dan
akan menurun sehingga tidak terdeteksi setelah hari sakit ke-5-6.
Deteksi antigen virus ini dapat digunakan untuk diagnosis awal
menentukan
adanya
infeksi
dengue,
namun
tidak
dapat
membedakan penyakit DD/DBD.
3. Uji serologi IgM dan IgG anti dengue
Antibodi IgM anti dengue dapat dideteksi pada hari sakit ke 35 sakit, mencapai puncaknya pada hari sakit ke 10-14, dan
akan menurun/ menghilang pada akhir minggu keempat sakit.
Antibodi IgG anti dengue pada infeksi primer dapat terdeteksi
pada minggu pertama. dan menghilang setelah 6 bulan sampai
4 tahun. Sedangkan pada infeksi sekunder IgG anti dengue
akan terdeteksi pada hari sakit ke-2.
Rasio IgM/IgG digunakan untuk membedakan infeksi primer
dari
infeksi
sekunder.
Apabila
rasio
IgM:IgG>1,2
menunjukkan infeksi primer namun apabila IgM:IgG rasio
<1,2 menunjukkan infeksi sekunder (WHO,2011).
Tabel 2. Interpretasi uji serologi IgM dan IgG pada infeksi dengue
Diagnosis
Antibodi anti dengue
IgM
Infeksi primer
Infeksi sekunder
Infeksi lampau
Bukan dengue
positif
positif
negatif
negatif
IgG
negatif
positif
positif
negatif
Keterangan
Apabila
mengarah
dengue,
klinis
ke
pada
infeksi
fase
penyembuhan: IgM dan
28
IgG diulang
Tabel 3. Derajat DBD berdasarkan klasifikasi WHO 2011
DD/DB
Derajat
Tanda dan gejala
D
Demam
Demam
Dengue
dengan 2 gejala
Laboratorium
minimal Leukopenia
disertai
leukosit
Nyeri kepala
Trombositopenia (jumlah
Nyeri otot, tulang/sendi
trombosit
Ruam kulit makulopapular
sel/mm3)
Tidak ada tanda perembesan
plasma
Demam
(5%-10%)
Tidak
ada
(uji
bendung <100.000
positif) dan tanda perembesan peningkatan
DBD
II
plasma
Seperti
derajat
<100.000
peningkatan
III
Seperti
derajat
atau
(nadi lemah, tekanan nadi 20 peningkatan
DBD*
IV
hipotensi,
sel/mm3,
hematokrit
sel/mm3,
hematokrit
20%
II Trombositopenia
ditambah kegagalan sirkulasi <100.000
mmHg,
bukti
20%
ditambah Trombositopenia
perdarahan spontan
DBD*
hematokrit
perembesan plasma
manifestasi Trombositopenia
dan
perdarahan
<100.000
Peningkatan
Manifestasi perdarahan
4000
sel/mm3)
Nyeri retro-orbital
DBD
(jumlah
sel/mm3;
hematokrit
gelisah, 20%
diuresis menurun
Syok hebat dengan tekanan Trombositopenia
darah dan nadi yang tidak <100.000
terdeteksi
peningkatan
20%
sel/mm3;
hematokrit
29
Diagnosis infeksi dengue:
Gejala klinis + trombositopenia + hemokonsentrasi, dikonfirmasi dengan deteksi
antigen virus dengue (NS-1) atau dan uji serologi anti dengue positif (IgM anti
dengue atau IgM/IgG anti dengue positif)
G. Komplikasi
1. Demam Dengue
Perdarahan dapat
terjadi
pada
pasien
dengan
ulkus
peptik,
trombositopenia hebat, dan trauma.
2. Demam Berdarah Dengue
Ensefalopati dengue dapat terjadi pada DBD dengan atau tanpa syok.
Kelainan ginjal akibat syok berkepanjangan dapat mengakibatkan
gagal ginjal akut.
Edema paru dan/ atau gagal jantung seringkali terjadi akibat
overloading pemberian cairan pada masa perembesan plasma
Syok yang berkepanjangan mengakibatkan asidosis metabolik &
perdarahan hebat (DIC, kegagalan organ multipel)
Hipoglikemia / hiperglikemia, hiponatremia, hipokalsemia akibat
syok berkepanjangan dan terapi cairan yang tidak sesuai.
Tanda tanda syok(UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, 2014):
- Anak gelisah sampai terjadi penurunan kesadaran, sianosis
- Nafas cepat, nadi teraba lembut kadang-kadang tak teraba
- Tekanan darah turun, tekanan nadi <10 mmHg
- Akral dingin, CRT menurun
- Diuresis menurun sampai anuria.
3.7 Tatalaksana
Terapi infeksi virus dengue dibagi menjadi 4 bagian, (1) Tersangka DBD, (2)
Demam Dengue (DD) (3) DBD derajat I dan II (4) DBD derajat III dan IV
(DSS).
1. Penatalaksanan DBD sesuai fase penyakit
30
Fase Demam
Pada fase demam, dapat diberikan antipiretik + cairan rumatan / atau
cairan oral apabila anak masih mau minum, pemantauan dilakukan
setiap 12-24 jam
a. Medikamentosa
1) Antipiretik dapat diberikan, dianjurkan pemberian parasetamol
apabila suhu 38C dengan interval 4-6 jam bukan aspirin.
2) Diusahakan tidak memberikan obat-obat yang tidak diperlukan
(misalnya antasid, anti emetik) untuk mengurangi beban
detoksifikasi obat dalam hati.
3) Kortikosteroid diberikan pada DBD ensefalopati apabila
terdapat
perdarahan
saluran
cerna
kortikosteroid
tidak
diberikan.
4) Antibiotik diberikan untuk DBD ensefalopati.
b. Supportif
Cairan: cairan pe oral + cairan intravena rumatan per hari + 5%
defisit Diberikan untuk 48 jam atau lebih. Kecepatan cairan IV
disesuaikan dengan kecepatan kehilangan plasma, sesuai keadaan
klinis, tanda vital, diuresis, dan hematokrit .
Fase Kritis
Pada fase kritis pemberian cairan sangat diperlukan yaitu kebutuhan
rumatan + deficit, disertai monitor keadaan klinis dan laboratorium
setiap 4-6 jam(WHO, 2011)
Terapi cairan pada DBD Grade III/Syok terkompensasi pada anak.
Syok pada infeksi dengue merupakan syok hipovolemik dengan fase
awal berupa syok terkompensasi dan fase selanjutnya adalah fase
dekompensasi.
31
Pada kondisi syok tak teratasi setelah pemberian cairan inisial, periksa
analisa gas darah, hematokrit, kalsium dan gula darah untuk menilai
kemungkinan
A-B-C-S
(A=asidosis,
B=bleeding/perdarahan,
C=calcium, S=Sugar/gula darah) yang memperberat syok hipovolemik.
Apabila salah satu atau beberapa kelainan tersebut ditemukan, segera
lakukan koreksi.
32
Terapi cairan pada DBD Grade IV/ Syok tak Terkompensasi
Pemantauan DBD dengan syok
1.
Tanda vital setiap 15-30 menit selama syok, selanjutnya setiap
jam apabila syok sudah teratasi
2.
Hematokrit harus diperiksa setiap sebelum pemberian cairan
resusitasi pertama dan kedua, selanjutnya tiap 4-6 jam
3.
Produksi urin
4.
syok dekompensasi atau prolonged: analisa gas darah, gula darah,
kalsium saat masuk RS
5.
Jika ditemukan gangguan fungsi organ lain, periksa segera.
6.
Pantau tanda-tanda kelebihan cairan yang bermanifestasi terhadap
edema paru, ascites, efusi pleura dan hepatomegali.
Perdarahan hebat
Apabila
sumber
perdarahan
dapat
diidentifikasi,
segera
hentikan.Transfusi darah segera adalah darurat tidak dapat ditunda
33
sampai hematokrit turun terlalu rendah.Bila darah yang hilang dapat
dihitung, harus diganti. Apabila tidak dapat diukur, 10 ml/kg darah
segar atau 5 ml/kg PRC harus diberikan dan dievaluasi.
Pada perdarahan saluran cerna, H2 antagonis dan penghambat pompa
proton dapat digunakan.
Tidak ada bukti yang mendukung penggunaan komponen darah seperti
suspense trombosit, plasma darah segar/cryoprecipitate.Penggunaan
larutan tersebut ini dapat menyebabkan kelebihan cairan(WHO,2011).
Fase Recovery
Pada fase penyembuhan diperlukan cairan rumatan atau cairan oral,
serta monitor tiap 12-24 jam.
Tanda tanda penyembuhan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Frekuensi nadi, tekanan darah dan frekuensi nafas stabil
Suhu badan normal
Tidak dijumpai oerdarahn baik eskternal maupun internal
Nafsu makan membaik
Tidak dijumpai muntah maupun nyeri perut
Volume urine cukup
Kadar hematocrit stabik pada kadar basal
Raum konvalesens, ditemukan 20% - 30% kasus. ( UKK Infeksi dan
Penyakit Tropis IDAI, 2014)
Indikasi untuk pulang
Pasien dapat dipulangkan apabila telah terjadi perbaikan klinis sebagai
berikut:
Bebas demam minimal 24 jam tanpa menggunakan antipiretik
Nafsu makan telah kembali
Perbaikan klinis, tidak ada demam, tidak ada distres pernafasan, dan
nadi teratur
Jumlah urin cukup
Minimum 2-3 hari setelah sembuh dari syok
Tidak ada kegawatan napas karena efusi pleura, tidak ada asites
Trombosit >50.000 /mm3. Apabila masih rendah namun klinis
baik,pasien boleh pulang dengan nasihat jangan melakukan aktivitas
yang memudahkan untuk mengalami trauma selama 1-2 minggu atau
penyakit lain yang menyertai, contoh: ITP. Pada kasus DBD tanpa
34
komplikasi umumnya jumlah trombosit akan meningkat ke nilai normal
dalam 3-5 hari(UKK, Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, 2014).
Konseling dan Edukasi
a. Prinsip konseling pada demam berdarah dengue adalah memberikan
pengertian kepada pasien dan keluarganya tentang perjalanan penyakit
dan tatalaksananya, sehingga pasien dapat mengerti bahwa tidak ada
obat/medikamentosa untuk penanganan DBD tetapi hanya bersifat
suportif dan mencegah perburukan penyakit. Penyakit akan sembuh
sesuai dengan perjalanan alamiah penyakit.
b. Modifikasi gaya hidup
1. Melakukan kegiatan 3M, menguras, mengubur, menutup.
2. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi
dan melakukan olehraga secara rutin.
Indikasi pemberian darah:
Terdapat perdarahan secara klinis;
-- Setelah pemberian cairan kristaloid dan koloid, syok menetap, hematokrit
turun, diduga telah terjadi perdarahan, berikan darah segar 10 ml/kgbb.
-- Apabila kadar hematokrit tetap > 40 vol%, maka berikan darah dalam
volume kecil.
-- Plasma segar beku dan suspensi trombosit berguna untuk koreksi gangguan
koagulopati atau koagulasi intravaskular desiminata (KID) pada syok berat
yang menimbulkan perdarahan masif.
-- Pemberian transfusi suspensi trombosit pada KID harus selalu disertai
plasma segar (berisi faktor koagulasi yang diperlukan), untuk mencegah
perdarahan lebih hebat.
DBD ensefalopati
Pada ensefalopati cenderung terjadi edema otak dan alkalosis, maka bila syok
telah teratasi, cairan diganti dengan cairan yang tidak mengandung HCO3-
35
dan jumlah cairan segera dikurangi. Larutan ringer laktat segera ditukar
dengan larutan NaCl (0,9%) : glukosa (5%) = 3:1.
Indikasi rawat
(lihat bagan 1)
Pemantauan
-
Tanda klinis, apakah syok telah teratasi dengan baik, adakah
pembesaran hati, tanda perdarahan saluran cerna, tanda ensefalopati,
harus dimonitor dan dievaluasi untuk menilai hasil pengobatan.
Kadar hemoglobin, hematokrit, dan trombosit tiap 6 jam, minimal tiap
12 jam.
Balans cairan, catat jumlah cairan yang masuk, diuresis ditampung,
dan jumlah perdarahan.
Pada DBD syok, lakukan cross match darah untuk persiapan transfusi
darah apabila diperlukan.
Indikasi pemberian cairan intravena
-
Pasien tidak dapat asupan yang adekuat untuk cairan per oral atau
muntah
Hematokrit meningkat 10%-20% meskipun dengan rehidrasi oral
Ancaman syok atau dalam keadaan syok
Prinsip umum terapi cairan pada DBD
-
Kristaloid isotonik harus digunakan selama masa kritis.
Cairan koloid digunakan pada pasien dengan perembesan plasma
hebat, dan tidak ada respon pada minimal volume cairan kristaloid
yang diberikan.
Volume cairan rumatan + dehidrasi 5% harus diberikan untuk menjaga
volume dan cairan intravaskular yang adekuat.
Pada pasien dengan obesitas, digunakan berat badan ideal sebagai
acuan untuk menghitung volume cairan.
36
Kecepatan cairan intravena harus disesuaikan dengan keadaan klinis.
Transfusi suspensi trombosit pada trombositopenia untuk profilaksis
tidak dianjurkan
Pemeriksaan laboratorium baik pada kasus syok maupun non syok saat
tidak ada perbaikan klinis walaupun penggantian volume sudah cukup,
maka perhatikan ABCS yang terdiri dari, A Acidosis: gas darah, B
Bleeding: hematokrit, C Calsium: elektrolit, Ca++ dan S Sugar:
gula darah (dekstrostik)
37
38
39
40
3.8 Komplikasi
Demam Dengue
Perdarahan dapat terjadi pada pasien dengan ulkus peptik, trombositopenia hebat,
dan trauma.
Demam Berdarah Dengue
Ensefalopati dengue dapat terjadi pada DBD dengan atau tanpa syok.
Kelainan ginjal akibat syok berkepanjangan dapat mengakibatkan gagal
ginjal akut.
41
Edema paru dan/ atau gagal jantung seringkali terjadi akibat overloading
pemberian cairan pada masa perembesan plasma
Syok yang berkepanjangan mengakibatkan asidosis metabolik &
perdarahan hebat (DIC, kegagalan organ multipel)
Hipoglikemia / hiperglikemia, hiponatremia, hipokalsemia akibat syok
berkepanjangan dan terapi cairan yang tidak sesuai
3.9 Diagnosis Banding
-
Selama fase akut penyakit, sulit untuk membedakan DBD dari demam
dengue dan penyakit virus lain yang ditemukan di daerah tropis. Maka
untuk membedakan dengan campak, rubela, demam chikungunya,
leptospirosis, malaria, demam tifoid, perlu ditanyakan gejala penyerta
lainnya yang terjadi bersama demam. Pemeriksaan laboratorium
diperlukan sesuai indikasi.
Penyakit darah seperti trombositopenia purpura idiopatik (ITP),
leukemia, atau anemia aplastik, dapat dibedakan dari pemeriksaan
laboratorium darah tepi lengkap disertai pemeriksaan pungsi sumsum
tulang apabila diperlukan.
Penyakit infeksi lain seperti sepsis, atau meningitis, perlu difikirkan
apabila anak mengalami demam disertai syok.
Anda mungkin juga menyukai
- Dengue Shock SyndromeDokumen27 halamanDengue Shock SyndromeAlvinHadisaputraBelum ada peringkat
- Demam Berdarah Dengue (DBD) DefinisiDokumen13 halamanDemam Berdarah Dengue (DBD) DefinisiWarni PutriBelum ada peringkat
- Referat DSS Dengue Syok SindromeDokumen21 halamanReferat DSS Dengue Syok SindromeRamdhan Akbar100% (1)
- Demam Berdarah Pada KehamilanDokumen21 halamanDemam Berdarah Pada Kehamilanjabolbol100% (1)
- Referat DHF Pada KehamilanDokumen22 halamanReferat DHF Pada KehamilanMuammar EduBelum ada peringkat
- Sindrom Syok Dengue MakalahDokumen16 halamanSindrom Syok Dengue MakalahsasmitadewaBelum ada peringkat
- Referat DHFDokumen19 halamanReferat DHFYudha PerwiraBelum ada peringkat
- Penegakan Diagnosis Demem Berdarah DengueDokumen18 halamanPenegakan Diagnosis Demem Berdarah DengueaquarossalindaBelum ada peringkat
- PDF Demam Berdarah Pada Kehamilan - CompressDokumen21 halamanPDF Demam Berdarah Pada Kehamilan - CompressNi Kadek GinantriBelum ada peringkat
- Laporan Kasus Dengue Shock SyndromeDokumen30 halamanLaporan Kasus Dengue Shock SyndromeCut Keumala Putri100% (1)
- Askep Dan Laporan PendahuluanDokumen9 halamanAskep Dan Laporan Pendahuluanhuzein pilantoBelum ada peringkat
- DBDDokumen21 halamanDBDfatmini lestariBelum ada peringkat
- Tinpus DHF Preskas 2Dokumen14 halamanTinpus DHF Preskas 2IntanBelum ada peringkat
- LP DBDDokumen13 halamanLP DBDMahfuzah RizzkiBelum ada peringkat
- Case Report DSSDokumen19 halamanCase Report DSSErvina Zelfi100% (1)
- Dengue Dan ChikungunyaDokumen27 halamanDengue Dan ChikungunyayuniBelum ada peringkat
- Laporan KasusDokumen40 halamanLaporan Kasusharry sondrio wibowoBelum ada peringkat
- LP Dengue Syok SindromDokumen20 halamanLP Dengue Syok Sindrom알댠가치Belum ada peringkat
- Sindrom Syok DengueDokumen32 halamanSindrom Syok DengueGeztu SasoriBelum ada peringkat
- DHF Teori Sudah FixDokumen31 halamanDHF Teori Sudah FixHennike FebriantiBelum ada peringkat
- DBDDokumen37 halamanDBDbismooBelum ada peringkat
- LP Anak DHF PicuDokumen18 halamanLP Anak DHF PicuPhebyBelum ada peringkat
- LP DBD - PiteeeDokumen15 halamanLP DBD - PiteeeNurfayantiBelum ada peringkat
- LP DBD WindaDokumen18 halamanLP DBD WindakepoxloloBelum ada peringkat
- Tinjauan Pustaka Demam BerdarahDokumen15 halamanTinjauan Pustaka Demam BerdarahSayu Putu DesyaBelum ada peringkat
- Tatalaksana DBD - Depkes 2007Dokumen48 halamanTatalaksana DBD - Depkes 2007Kartika Soka Rahmita Dachlan0% (1)
- LP DBD Auliaihsan 183110244 3.c-1Dokumen25 halamanLP DBD Auliaihsan 183110244 3.c-1Famelya SyafrilinaBelum ada peringkat
- LP DBD - NinaDokumen28 halamanLP DBD - NinaronaBelum ada peringkat
- ASKEP DHFDokumen28 halamanASKEP DHFnurjama680Belum ada peringkat
- EpidemiologiDokumen20 halamanEpidemiologiIsom GallardoBelum ada peringkat
- Mikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaDari EverandMikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaPenilaian: 2.5 dari 5 bintang2.5/5 (2)
- Mikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaDari EverandMikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (11)
- Coronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Dari EverandCoronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Konsensus SkizofreniaDokumen94 halamanKonsensus SkizofreniaFika Amalia67% (3)
- Itp FixDokumen28 halamanItp FixHanarisha Putri AzkiaBelum ada peringkat
- Follow Up Pasien Dokter MudaDokumen3 halamanFollow Up Pasien Dokter MudaHanarisha Putri AzkiaBelum ada peringkat
- Tanda - Tanda Hipertension Heart Disease: Oleh: Dwi Erin NPM: 1618012011Dokumen7 halamanTanda - Tanda Hipertension Heart Disease: Oleh: Dwi Erin NPM: 1618012011Hanarisha Putri AzkiaBelum ada peringkat