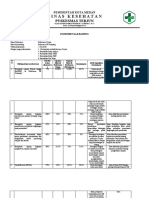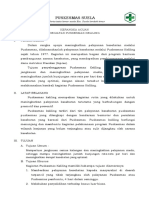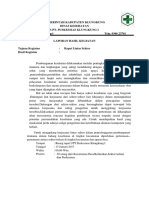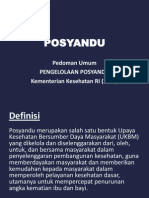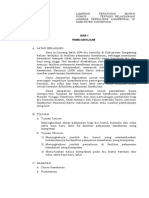Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stuntin
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stuntin
Diunggah oleh
adibjnHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stuntin
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stuntin
Diunggah oleh
adibjnHak Cipta:
Format Tersedia
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat
2017
Modul Pelatihan
Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) – Stunting
Kata Pengantar Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat Kementerian Kesehatan
Daftar Isi
Kata Pengantar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan ii
MODUL DASAR 8
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
DENGAN STBM 8
I. DESKRIPSI SINGKAT 8
II. TUJUAN PEMBELAJARAN 9
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 9
IV. METODE 9
V. MEDIA DAN ALAT BANTU 9
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 9
VII. URAIAN MATERI 10
POKOK BAHASAN 1: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 10
A. Konsep Pembangunan Kesehatan.........................................................................10
B. Pendekatan Keluarga dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan
12
C. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat...........................................................................13
POKOK BAHASAN 2: GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI..........14
POKOK BAHASAN 3: KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL STBM.........................18
VIII. REFERENSI 18
MODUL MI.1 20
KONSEP DASAR STBM-STUNTING 20
I. DESKRIPSI SINGKAT 20
II. TUJUAN PEMBELAJARAN 20
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 20
IV. METODE 21
V. MEDIA DAN ALAT BANTU 21
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 21
VII. URAIAN MATERI 26
POKOK BAHASAN 1: STUNTING 26
A. Pengertian Stunting....................................................................................................26
B. Penyebab Stunting.....................................................................................................27
C. Akibat Stunting............................................................................................................30
POKOK BAHASAN 2 : PENCEGAHAN STUNTING..............................................................30
A. Pendekatan secara langsung/intervensi gizi spesifik........................................30
B. Pendekatan secara tidak langsung/intervensi gizi sensitif..............................31
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman i
POKOK BAHASAN 3: KONSEP STBM 34
A. Pengertian STBM........................................................................................................34
B. Tujuan STBM................................................................................................................34
C. Sejarah Program Pembangunan Sanitasi.............................................................34
POKOK BAHASAN 4: PRINSIP-PRINSIP STBM-STUNTING.............................................36
A. Tanpa subsidi...............................................................................................................37
B. Masyarakat sebagai pemimpin................................................................................38
C. Tidak menggurui/memaksa......................................................................................38
D. Totalitas.........................................................................................................................39
POKOK BAHASAN 5: STRATEGI STBM-STUNTING...........................................................39
A. Peningkatan Kebutuhan dan Permintaan Sanitasi-Stunting............................39
B. Peningkatan Layanan Penyediaan Sanitasi dan Pencegahan Stunting........39
C. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif................................................................40
POKOK BAHASAN 6: DELAPAN PILAR STBM-STUNTING...............................................41
A. Pengertian pilar – pilar dalam STBM-Stunting.....................................................41
B. Penyelenggaraan pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting......................................51
C. Manfaat pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting.......................................................51
D. Tujuan Pelaksanaan 8 Pilar STBM-Stunting.........................................................51
POKOK BAHASAN 7: TANGGA PERUBAHAN PERILAKU VISI STBM-STUNTING......52
A. Tangga Perubahan Perilaku Sanitasi.....................................................................52
1. Perilaku BABS.................................................................................................................53
2. Perilaku SBS....................................................................................................................54
3. Perilaku Higienis dan Saniter.......................................................................................54
4. Perilaku Sanitasi Total...................................................................................................54
B. Tangga perubahan perilaku asupan gizi...............................................................54
C. Tangga perubahan perilaku visi STBM-Stunting.................................................56
VIII. REFERENSI 58
IX. LAMPIRAN (Terlampir) 58
MODUL MI.2 59
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM STBM-STUNTING 59
I. DESKRIPSI SINGKAT 59
II. TUJUAN PEMBELAJARAN 59
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 59
IV. METODE 60
V. MEDIA DAN ALAT BANTU 60
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 60
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman ii
VII. URAIAN MATERI 63
POKOK BAHASAN 1: PARTISIPASI MASYARAKAT 63
A. Pengertian Partisipasi Masyarakat.........................................................................63
B. Tingkatan Partisipasi Masyarakat...........................................................................63
POKOK BAHASAN 2: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM STBM-STUNTING..64
A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.................................................................64
B. Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat............................................................64
C. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....................................................................65
D. Penerapan Pemberdayaan Masyarakat dalam STBM-Stunting.......................66
VIII. REFERENSI 68
IX. LAMPIRAN (Terlampir) 68
MODUL MI.3 69
KOMUNIKASI, ADVOKASI, DAN FASILITASI STBM-STUNTING 69
I. DESKRIPSI SINGKAT 69
II. TUJUAN PEMBELAJARAN 69
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 69
IV. METODE PEMBELAJARAN 70
V. MEDIA DAN ALAT BANTU 70
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 70
VII. URAIAN MATERI 74
POKOK BAHASAN 1: KOMUNIKASI STBM-STUNTING 74
POKOK BAHASAN 2: ADVOKASI STBM-STUNTING 80
A. Pengertian Advokasi..................................................................................................80
B. Cara Melakukan Advokasi yang Efektif.................................................................81
C. Langkah-Langkah Advokasi STBM-Stunting.......................................................82
POKOK BAHASAN 3: TEKNIK FASILITASI STBM-STUNTING.....................................85
A. Prinsip-Prinsip Fasilitasi STBM-Stunting..............................................................85
1. Pengertian Fasilitasi.......................................................................................................85
2. Prinsip Dasar Fasilitasi..................................................................................................85
3. Peran Fasilitator..............................................................................................................87
4. Perilaku Fasilitator dalam STBM-Stunting................................................................89
B. Teknik-Teknik Fasilitasi.............................................................................................91
1. Teknik Mendengar...........................................................................................................91
2. Teknik Bertanya...............................................................................................................95
3. Teknik Menghadapi Situasi Sulit.................................................................................99
4. Dinamika Bertanya.......................................................................................................100
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman iii
5. Curah Pendapat.............................................................................................................100
VIII. REFERENSI 101
IX. LAMPIRAN (Terlampir) 101
MODUL MI.4 102
PEMICUAN STBM-STUNTING DI KOMUNITAS 102
I. DESKRIPSI SINGKAT 102
II. TUJUAN PEMBELAJARAN 102
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 102
IV. METODE BAHAN BELAJAR 102
V. MEDIA DAN ALAT BANTU 102
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 103
VII. URAIAN MATERI 105
POKOK BAHASAN 1: KEGIATAN PRA PEMICUAN 105
A. Observasi PHBS dan screening faktor resiko stunting...................................105
B. Persiapan Pemicuan dan Menciptakan Suasana yang Kondusif Sebelum
Pemicuan................................................................................................................................106
C. Persiapan Teknis dan Logistik...............................................................................106
POKOK BAHASAN 2: PEMICUAN 107
A. Pengantar....................................................................................................................107
B. Alat-Alat utama untuk Pemicuan...........................................................................107
C. Elemen Pemicuan dan Faktor Penghambat Pemicuan....................................113
D. Langkah-langkah Pemicuan di Komunitas.........................................................116
POKOK BAHASAN 3: PASKA PEMICUAN......................................................................117
A. Cara Membangun Ulang Komitmen......................................................................117
B. Pilihan Teknologi Sanitasi untuk 8 Pilar STBM-Stunting................................117
C. Membangun Jejaring Layanan Penyediaan Sanitasi dan Gizi.......................118
D. Pendampingan dan Monitoring,............................................................................119
E. Menggali media promosi untuk perubahan perilaku yang berkelanjutan.......128
VIII. DAFTAR PUSTAKA 128
IX. LAMPIRAN (Terlampir) 128
MODUL PENUNJANG 1 129
MEMBANGUN KOMITMEN BELAJAR (BLC) 129
I. DESKRIPSI SINGKAT 129
II. TUJUAN PEMBELAJARAN 129
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 129
IV. METODE 130
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman iv
V. MEDIA DAN ALAT BANTU 130
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 130
VII. URAIAN MATERI 132
POKOK BAHASAN 1: PERKENALAN 132
POKOK BAHASAN 2: PENCAIRAN132
POKOK BAHASAN 3: HARAPAN-HARAPAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN
HASIL YANG INGIN DICAPAI 132
POKOK BAHASAN 4: NORMA KELAS DALAM PEMBELAJARAN 133
POKOK BAHASAN 5: KONTROL KOLEKTIF DALAM PELAKSANAAN NORMA KELAS
134
POKOK BAHASAN 6: ORGANISASI KELAS 134
VIII. REFERENSI 134
IX. LAMPIRAN (Terlampir) 134
MODUL PENUNJANG 2 135
ANTI KORUPSI 135
I. DESKRIPSI SINGKAT 135
II. TUJUAN PEMBELAJARAN 135
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 135
IV. METODE 136
V. MEDIA DAN ALAT BANTU 136
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 136
VII. URAIAN MATERI 137
POKOK BAHASAN 1 : KONSEP KORUPSI 137
A. Definisi Korupsi.........................................................................................................137
B. Ciri-ciri Korupsi.........................................................................................................138
C. Jenis/Bentuk Korupsi...............................................................................................138
D. Tingkatan Korupsi....................................................................................................139
E. Tingkatan Korupsi........................................................................................................140
F. Dasar Hukum Tentang Korupsi.................................................................................141
POKOK BAHASAN 2: KONSEP ANTI KORUPSI 142
A. Anti Korupsi...............................................................................................................142
B. Nilai-Nilai Anti Korupsi............................................................................................142
C. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi..................................................................................145
POKOK BAHASAN 3: UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 147
A. Upaya Pencegahan Korupsi...................................................................................148
POKOK BAHASAN 4: TATA CARA PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK
PIDANA KORUPSI 153
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman v
POKOK BAHASAN 5: GRATIFIKASI 156
POKOK BAHASAN 6: KASUS-KASUS KORUPSI 159
VIII. REFERENSI 161
IX. LAMPIRAN (Terlampir) 161
MODUL PENUNJANG 3 162
RENCANA TINDAK LANJUT 162
I. DESKRIPSI SINGKAT 162
II. TUJUAN PEMBELAJARAN 162
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 162
IV. METODE 162
V. MEDIA DAN ALAT BANTU 162
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 162
VII. URAIAN MATERI 163
POKOK BAHASAN 1 : RENCANA TINDAK LANJUT 163
a. Pengertian Rencana Tindak Lanjut..........................................................................164
b. Ruang Lingkup Rencana Tindak Lanjut (RTL).......................................................164
POKOK BAHASAN 2. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RTL. 164
POKOK BAHASAN 3 : PENYUSUNAN RTL DAN GANTT CHART UNTUK KEGIATAN
YANG AKAN DILAKUKAN 166
a. Penyusunan RTL...........................................................................................................166
b. Gantt Chart.....................................................................................................................167
POKOK BAHASAN 4 : EVALUASI PELAKSANAAN STBM-STUNTING 167
VIII. REFERENSI 168
IX. LAMPIRAN (Terlampir) 168
Daftar Tabel
Tabel 1. Kecenderungan Pelaksanaan Program Air dan Sanitasi di Indonesia.......................35
Tabel 2: Inventarisasi Pemangku Kepentingan dan Kegiatan Advokasi STBM-Stunting........84
Tabel 3: Pemilihan Isu Advokasi.....................................................................................................85
Tabel 4: Fasilitasi yang Harus Dilakukan dan Dihindari dalam STBM-Stunting.......................93
Tabel 5. Kiat Menciptakan Pertanyaan yang Indah..............................................................................98
Tabel 6: Intervensi Menghadapi Situasi Sulit..............................................................................100
Tabel 7. Faktor Resiko Stunting dan Upaya Pencegahannya...............................................................110
Tabel 8. Kerangka Pikir Pemicuan STBM-Stunting....................................................................113
Tabel 9. Elemen Pemicuan dan Alat Partisipatif yang Digunakan............................................114
Tabel 10. Faktor Penghambat Pemicuan dan Solusi yang Disarankan..................................115
Tabel 11. Alur Pikir Tata Laksana monitoring dan pelaporan dari masyarakat hingga tingkat
pusat....................................................................................................................................123
Tabel 12. Model Pelaksanaan Monitoring di Masyarakat................................................... 124
Tabel 13. Model Pelaksanaan Monitoring di tingkat Puskesmas....................................... 126
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman vi
Tabel 14. Jenis/Bentuk Korupsi.....................................................................................................140
Daftar Gambar
Gambar 1. Skema Kerangka dan Struktur Kebijakan Pembangunan Kesehatan...................13
Gambar 2. Situasi Gizi di Indonesia...............................................................................................16
Gambar 3. Akses Jamban dan Prevalensi Stunting di Indonesia..............................................17
Gambar 4. Anak Stunting.................................................................................................................28
Gambar 5. Kerangka Pikir Penyebab Masalah Kesehatan Gizi.................................................29
Gambar 6. Alur Hubungan Hygiene-Sanitasi dan Gizi...........................................................30
Gambar 7. Diagram Pemutusan Mata Rantai Penularan Diare untuk Mencegah Stunting....34
Gambar 8. Aksi-Aksi Agar Gizi dan Perkembangan Janin dan Anak Optimal..........................35
Gambar 9. Kriteria Jamban Sehat..................................................................................................43
Gambar 10. Tangki septik cor langsung tanpa sambungan........................................................44
Gambar 11 Tangga Perubahan Perilaku........................................................................................53
Gambar 12 Tangga Perubahan perilaku STBM............................................................................54
Gambar 13 Tangga Perubahan Perilaku STBM-Stunting............................................................58
Gambar 14: Alur Proses Mengembangan Konsep-Konsep Komunikasi Perubahan Perilaku. 85
Gambar 15: Pengemasan Materi Advokasi...................................................................................90
Gambar 16: Peran Fasilitator..........................................................................................................93
Gambar 17: Tiga Pilar Utama Perubahan Perilaku dalam Pendekatan Partisipatif.................95
Gambar 18. Teknik Bertanya..............................................................................................................102
Gambar 19. ALur Penularan Penyakit (Diagram F) dan Stunting......................................120
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman vii
MODUL DASAR
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM PERCEPATAN
PERBAIKAN GIZI DENGAN STBM
I. DESKRIPSI SINGKAT
Materi ini berisi uraian tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang telah
ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Gerakan
nasional percepatan perbaikan gizi, serta Kebijakan dan Strategi Nasional STBM.
Kebijakan tersebut diatas salah satunya ditujukan untuk penanganan permasalahan
gizi khususnya stunting. Stunting merupakan akibat dari kekurangan gizi pada jangka
panjang yang menyebabkan gangguan intelektual dan pertumbuhan linier (Waterlow,
1972). Di Indonesia sekitar 37% atau hampir 9 juta anak balita mengalami stunting,
(Riskesdas 2013) dan merupakan prevalensi stunting terbesar ke 5 di dunia.
Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tahun
2016 menemukan bahwa 27,5% anak dibawah lima tahun (balita) dan sebesar
21,7% anak dibawah dua tahun mengalami stunting. Hal ini menyebabkan mereka
mudah sakit, memiliki postur tubuh yang lebih pendek dari balita seusianya, tidak
memiliki kemampuan kognitif yang memadai, sehingga tidak saja merugikan bagi
individu tetapi juga merugikan kondisi sosial ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.
Berbagai studi dan analisis yang dilakukan oleh akademisi, Kemenkes, WHO, Bank
Dunia, maupun UNICEF menemukan keterkaitan antara ketersediaan akses sanitasi
yang layak dan stunting. Riskesdas 2013 menunjukkan daerah yang memiliki akses
sanitasi yang rendah cenderung memiliki kasus stunting yang lebih tinggi. Studi
Lancet (2013) menemukan bahwa intervensi gizi spesifik, termasuk melalui
ketersediaan akses air minum dan sanitasi yang layak, dapat mengurangi prevalensi
stunting hingga 20%. Diterapkannya pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) oleh Kemenkes sejak 2008 telah meningkatkan akses sanitasi dari 48,56%
di tahun 2008 ke 67,80% di tahun 2016. Diadopsinya pendekatan STBM ke dalam
program-program air minum juga telah berkontribusi pada peningkatan akses dari
46,45% tahun 2008 ke 71,14% di tahun 2016. Masih ada sekitar 80 juta penduduk
Indonesia yang belum memiliki akses sanitasi yang layak dan 74 juta yang belum
memiliki akses air minum yang layak (BPS, 2017).
Pembangunan Kesehatan tahun 2015-2019 merupakan suatu upaya untuk
mewujudkan Nawacita ke-5 Presiden Republik Indonesia, yakni meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia. Upaya tersebut dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diperinci dalam Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) 2015-2019. Kebijakan
tersebut merupakan dasar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan acuan
dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dalam melaksanakan pembangunan
kesehatan, khususnya terkait dengan stunting, Indonesia juga tidak terlepas dari
komitmen global, khususnya program Scaling Up Nutrition (SUN). Penanganan
stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat
umum dan lainnya. Presiden dan wakil presiden berkomitmen untuk memimpin
langsung upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat
dipercepat dan dapat terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah
berkomitmen melakukan upaya penanggulangan stunting di seluruh wilayah
kabupaten/kota pada tahun 2021. Saat ini yang menjadi prioritas di 100
kabupaten/kota tahun 2017-2018.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 8
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu memahami Kebijakan Pembangunan
Kesehatan untuk percepatan perbaikan gizi dengan STBM.
B. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:
1. Menjelaskan kebijakan pembangunan kesehatan;
2. Menjelaskan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi; dan
3. Menjelaskan kebijakan dan strategi nasional STBM.
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai
berikut:
A. Pokok Bahasan 1: Kebijakan Pembangunan Kesehatan
a. Konsep Pembangunan Kesehatan;
b. Pendekatan keluarga dalam pencapaian prioritas pembangunan kesehatan;
dan
c. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
B. Pokok Bahasan 2: Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
C. Pokok Bahasan 3: Kebijakan dan Strategi Nasional STBM
IV. METODE
Ceramah Tanya jawab (CTJ).
V. MEDIA DAN ALAT BANTU
Bahan tayang (slide power point), computer, LCD proyektor, sound system, flipchart,
spidol (ATK), metaplan, modul.
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 2 jam pelajaran (T=2
jpl, P=0 jpl, dan PL=0 JPL) @45 menit. Untuk mempermudah proses pembelajaran
dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta, dilakukan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut:
Langkah 1. Pengkondisian (10 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Fasilitator memulai kegiatan dengan melakukan bina suasana di kelas.
b. Fasilitator menyampaikan salam serta menyapa peserta dengan ramah dan
hangat.
c. Fasilitator memperkenalkan diri.
2. Kegiatan Peserta
a. Mempersiapkan diri dan alat tulis bila diperlukan.
b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan.
Langkah 2. Pembahasan per materi (70 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Menggali pendapat peserta tentang kebijakan pembangunan kesehatan.
b. Menyampaikan pokok bahasan dan sub pokok bahasan dengan metode CTJ.
c. Menjawab pertanyaan dari peserta.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 9
2. Kegiatan Peserta
a. Memberikan pendapat dari pertanyaan fasilitator.
b. Mendengar dan mencatat hal-hal yang penting dalam materi.
c. Mengajukan pertanyaan kepada fasilitator bila masih ada yang belum
dipahami.
Langkah 3. Rangkuman (10 Menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Merangkum sesi pembelajaran.
b. Mempersilahkan peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas.
c. Memfasilitasi pemberian jawaban, baik dari fasilitator maupun peserta lain.
d. Meminta komentar, penilaian, saran, dan kritik dari peserta pada kertas
evaluasi yang telah disediakan.
e. Menutup sesi pembelajaran dengan memastikan TPU dan TPK telah
tercapai.
2. Kegiatan Peserta.
a. Mencatat hal-hal yang pening dalam rangkuman.
b. Berpartisipasi aktif untuk memberikan pertanyaan, masukan, penilaian, saran,
dan kritik.
VII. URAIAN MATERI
POKOK BAHASAN 1: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Arah kebijakan pembangunan kesehatan yang menjadi fokus perhatian nasional saat ini
adalah memperkuat upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit
(preventif) dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan upaya percepatan
perbaikan gizi masyarakat melalui 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
A. Konsep Pembangunan Kesehatan
Pembanguan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan kesehatan.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1, kesehatan
adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Sedangkan pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan ke arah yang
lebih baik di masyarakat.
Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009
tentang Kesehatan Pasal 3, untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi pembangunan sumber daya
manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar
upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah
dilaksanakan dalam periode sebelumnya.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat
dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui
upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran tersebut sesuai dengan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 10
sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019, yaitu:
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di
daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui kartu indonesia
sehat (KIS) dan kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
kesehatan;
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin, serta
6. Meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yang ditujukan kepada
tercapainya keluarga sehat yaitu: 1. Paradigma sehat, 2. Penguatan pelayanan
kesehatan, dan 3. Jaminan kesehatan nasional.
1. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan
dalam pembangunan, penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan
masyarakat;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses
pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care, dan intervensi berbasis
risiko kesehatan;
3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan dengan strategi perluasan sasaran
dan manfaat (benefit), serta kendali mutu dan kendali biaya.
Dalam bentuk skema, kerangka, dan struktur kebijakan Pembangunan Kesehatan
tersebut adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Skema Kerangka dan Struktur Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 11
Dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan
telah menetapkan kebijakan operasional dalam periode 2015-2019 difokuskkan pada
prioritas:
1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
2. Perbaikan gizi masyarakat khususnya untuk pengendalian prevalensi balita pendek
(stunting) (ditargetkan pada tahun 2019 stunting pada anak dibawah dua tahun
(baduta) sebesar 28%);
3. Pengendalian penyakit menular khususnya Human Immunodeficiency Virus-
Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS), Tuberkulosis (TB), dan Malaria;
4. Pengendalian penyakit tidak menular khususnya hipertensi, diabetes melitus,
obesitas, kanker, dan gangguan jiwa.
Salah satu prioritas pembangunan kesehatan yang telah disebutkan diatas adalah
upaya penurunan prevalensi balita pendek stunting, sehingga pencegahan dan
penanggulangan stunting menjadi sangat penting. Dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan stunting, maka fokus perhatian diberikan kepada periode 1000 Hari
Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa pembuahan, kehamilan, kelahiran,
sampai bayi berusia 2 tahun.
B. Pendekatan Keluarga dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Kesehatan
Upaya pencapaian prioritas pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 dalam Program
Indonesia Sehat dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada,
baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat.
Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga.
Pembangunan keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 52
Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah upaya
mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pemerintah
pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, untuk mendukung keluarga agar
dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Sebagai penjabaran dari amanat
Undang-Undang tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan strategi operasional
pembangunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga.
Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan
jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya dengan mendatangi setiap keluarga. Puskesmas tidak hanya
menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan keluar gedung
dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya (family outreach). Kunjungan rumah
(keluarga) dilakukan secara terjadwal dan rutin, dengan memanfaatkan data dan
informasi dari Profil Kesehatan Keluarga (family folder).
Pentingnya pendekatan keluarga juga diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Dalam Renstra disebutkan bahwa salah
satu acuan bagi arah kebijakan Kementerian Kesehatan adalah melalui pendekatan
upaya pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan (continuum of
care). Hal ini berarti bahwa pelayanan kesehatan harus dilakukan terhadap seluruh
tahapan siklus hidup manusia (life cycle), sejak masih dalam kandungan, sampai lahir
menjadi bayi, tumbuh menjadi anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa muda
(usia produktif), dan menjadi dewasa tua (usia lanjut). Dalam pemberian pelayanan
kesehatan, individu-individu harus dilihat dan diperlakukan sebagai bagian dari
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 12
keluarganya yang selanjutnya dilihat secara keseluruhan menjadi komponen
masyarakat.
Pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah ini tidak berarti mematikan Upaya
Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada seperti Posyandu atau komite-
komite kesehatan khusus lainnya, tetapi justru untuk memperkuat UKBM-UKBM yang
selama ini dirasakan masih kurang efektif.
Dengan mengunjungi keluarga di rumahnya, Puskesmas akan dapat mengenali
masalah-masalah kesehatan termasuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang
dihadapi keluarga secara lebih menyeluruh (holistik). Individu anggota keluarga yang
perlu mendapatkan pelayanan kesehatan kemudian dimotivasi untuk memanfaatkan
UKBM yang ada dan/atau pelayanan Puskesmas. Keluarga juga dimotivasi untuk
memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan yang berkontribusi juga terhadap kejadian
stunting dan faktor-faktor risiko lain yang selama ini merugikan kesehatannya, dengan
pendampingan dari kader-kader kesehatan UKBM dan/atau petugas profesional
Puskesmas. Untuk itu, diperlukan pengaturan agar setiap keluarga di wilayah
Puskesmas memiliki Tim Pembina Keluarga.
Dalam rangka upaya penurunan stunting, pendekatan keluarga ditujukan untuk menjaga
kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya sampai anak berusia 2 (dua) tahun
termasuk perubahan perilaku dan perbaikan lingkungan, apabila terdapat komplikasi
atau faktor risiko diupayakan dapat dideteksi secara dini dan dilakukan intervensi.
Kesehatan janin dalam kandungan dan bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada
kondisi kesehatan dan gizi ibu hamil, sebelum hamil bahkan sebelum menikah. Oleh
karena itu, intervensi penanganan stunting dilakukan juga kepada remaja untuk
mempersiapkan remaja menjadi calon pengantin dan ibu hamil dalam kondisi kesehatan
dan gizi yang optimal.
C. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat perlu dilakukan
secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat yang lebih baik.
GERMAS merupakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dicanangkan oleh
Presiden yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh instansi dengan tujuan
akhirnya adalah pemberdayaan kesehatan masyarakat. Germas adalah suatu tindakan
sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen
bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk
meningkatkan kualitas hidup melalui:
1. Peningkatan aktivitas fisik;
2. Peningkatan perilaku hidup sehat;
3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
5. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
6. Peningkatan edukasi hidup sehat.
Fokus kegiatan GERMAS tahun 2017 adalah melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur
dan buah serta memeriksa kesehatan secara berkala.
Tujuan GERMAS adalah agar masyarakat berperilaku sehat dan diharapkan kesehatan
masyarakat terjaga, terciptanya lingkungan yang bersih sehingga jika masyarakat sehat
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 13
maka produktivitas masyarakat akan meningkat serta secara tidak langsung akan
mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk berobat.
Sasaran GERMAS adalah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu, keluarga
serta elemen masyarakat lainnya harus terlibat dengan prinsip dan pendekatan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah fokus pada pemerataan intervensi,
pentingnya kerjasama multisektor dan para pemangku kepentingan, keseimbangan
masyarakat, keluarga dan individu, pemeberdayaan masyarakat, penguatan sistem
kesehatan, pendekatan siklus kehidupan, selaras dengan implementasi Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), dan strategi atau rencana kegiatan berdasarkan bukti.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran GERMAS maka perlu diterapkan strategi dalam
pelaksanaan yaitu:
a. Koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor: Melakukan koordinasi
dengan lintas sektor atau SKPD lainnya dalam menyosialisasikan GERMAS
b. Advokasi: Melakukan advokasi ke pembuat keputusan baik ke Pemerintah Daerah
maupun sektor BUMN, BUMD, swasta, organisasi masyarakat, dll.
c. Penggerakkan masyarakat melalui pendekatan Keluarga Sehat
d. Pendekatan siklus hidup.
POKOK BAHASAN 2: GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN
GIZI
Saat ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, di satu pihak mengalami
kekurangan gizi tetapi di pihak lain mengalami kelebihan gizi.
Gambar 2. Situasi Gizi di Indonesia
Terdapat banyak penyebab yang mempengaruhi status gizi, dua faktor penyebab
langsung adalah kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi. Keduanya
saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak kekurangan gizi maka daya
tahan tubuh akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi selanjutnya
jatuh pada kondisi kekurangan gizi, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit
infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah.
Di Indonesia sanitasi yang buruk merupakan isu penting yang berhubungan dengan
meningkatnya resiko penyakit infeksi yang dapat menyebabkan stunting. Hasil Riskedas
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 14
tahun 2013 menunjukan adanya hubungan antara sanitasi yang buruk dengan stunting,
terdapat kencenderungan bahwa provinsi yang memiliki proporsi rumah tangga dengan
akses sanitasi yang lebih baik memiliki presentase stunting yang lebih rendah.
Gambar 3. Akses Jamban dan Prevalensi Stunting di Indonesia
Menurut Global Nutrition Report 2014, Indonesia termasuk dalam 17 negara diantara
117 negara yang mempunyai ketiga masalah stunting, wasting, dan overweight pada
balita. Indonesia juga termasuk didalam 47 Negara dari 112 Negara yang mempunyai
masalah stunting pada balita dan anemia pada Wanita Usia Subur (WUS).
Dalam mengatasi masalah gizi maka perlu memperhatikan continum of care, mulai dari
1000 HPK, anak balita, remaja, dewasa, sampai dengan usia lanjut. Gerakan perbaikan
gizi yang fokus terhadap 1000 HPK pada tataran global disebut Scaling Up Nutrition
(SUN) dan di Indonesia disebut dengan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi
dalam rangka 1000 HPK.
Indonesia berkontribusi terhadap pencapaian target global dalam Scaling Up Nutrition
(SUN) movement pada akhir tahun 2025 yaitu:
1. Menurunkan proporsi anak balita yang stunting sebesar 40 persen;
2. Menurunkan proporsi anak balilta yang menderita kurus (wasting) kurang dari 5
persen;
3. Menurunkan anak yang lahir berat badan rendah sebesar 30 persen;
4. Tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih;
5. Menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50 persen;
dan
6. Meningkatkan prosentase ibu yang memberikan ASI ekslusif selama 6 bulan paling
kurang 50 persen.
Upaya perbaikan gizi tercantum dalam Bab VIII, Pasal 141, ayat (1) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009, ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perorangan dan
masyarakat. Selanjutnya di dalam percepatan perbaikan gizi, pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi yang fokus pada 1000 HPK.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 15
Gerakan nasional percepatan perbaikan gizi adalah upaya bersama antar
pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian
pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan
gizi masyarakat prioritas pada seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak
terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun, yang
merupakan sebuah fase perkembangan manusia yang terbentuk sejak masa konsepsi
(pembuahan) dan tumbuh menjadi janin di dalam masa kehamilan (270 hari) sampai
dengan usia anak 2 tahun pertama (730 hari). Periode ini menjadi satu tahapan penting
(critical moment), terutama dalam pembentukan masa emas (golden period). Periode
1000 HPK telah dibuktikan secara ilmiah merupakan periode yang menentukan kualitas
kehidupan, oleh karena itu periode ini disebut sebagai “periode emas” atau dikenal
sebagai window of opportunity.
Gerakan nasional percepatan perbaikan gizi bertujuan untuk percepatan perbaikan gizi
masyarakat dengan prioritas pada 1000 HPK dengan meningkatkan komitmen para
pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi
masyarakat, meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi khususnya
koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi, dan memperkuat
implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.
Gerakan nasional percepatan perbaikan gizi mengedepankan upaya bersama antara
pemerintah dengan elemen masyarakat melalui kegiatan penggalangan partisipasi dan
kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk
percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas pada 1000 HPK.
Komitmen para pemangku kepentingan berupa:
1. Tingkat Nasional
Dibentuk gugus tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi melalui
Perpres. Gugus tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden serta dipimpin oleh Menkokesra dengan anggota Menteri terkait yang
dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis.
2. Tingkat Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk gugus tugas di
tingkat daerah untuk menyusun rencana dan program kerja dengan mengacu
pada kebijakan nasional. Anggota gugus tugas daerah terdiri dari: Pemerintah
Daerah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan,
Organisasi Keagamaan, Dunia Usaha, dan anggota Masyarakat.
Strategi utama gerakan nasional percepatan perbaikan gizi meliputi:
1. Menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya
manusia, sosial budaya, dan perekonomian;
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor
baik pemerintah maupun swasta;
3. Peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang
ada di masyarakat; dan
4. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang
mendukung perilaku sadar gizi.
Sasaran gerakan nasional percepatan perbaikan gizi meliputi:
1. Masyarakat khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak dibawah usia
dua tahun;
2. Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, pemberdayaan kesejahteraan
keluarga, dan/atau kader masyarakat yang sejenis;
3. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 16
4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Media massa;
6. Dunia usaha; dan
7. Lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan internasional.
Dalam rangka mendukung percepatan program 1000 HPK melalui komitmen lintas
sektor, maka pemerintah Indonesia menetapkan arah kebijakan 2015-2019, mencakup:
1. Peningkatan surveillans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;
2. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, dll;
3. Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi;
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi;
5. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi; serta
6. Penguatan lintas sektor dalam rangka intervensi gizi sensitif dan spesifik.
Penanganan stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat
umum dan lainnya. Presiden dan wakil presiden berkomitmen untuk memimpin langsung
upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan
dapat terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini upaya penanggulangan
stunting menjadi prioritas di 100 kabupaten/kota tahun 2017-2018
Menurut Lancet series (2013), intervensi gizi spesifik terbukti jika dilaksanakan bersama-
sama dalam skala besar (cakupan mencapai 90%) dapat mengurangi prevalensi stunting
sebesar 20%. Penurunan masalah gizi secara berkelanjutan membutuhkan intervensi
yang terpadu dan tidak hanya melalui intervensi gizi spesifik. Intervensi ini disebut
dengan intervensi gizi sensitif.
Intervensi gizi Sensitif dan Intervensi Spesifik
Percepatan kelanjutan di bidang gizi akan lebih efektif melalui intervensi sensitif yang
lebih luas yang ditujukan untuk mengurangi penyebab tidak langsung dan intervensi
spesifik.
Intervensi gizi spesifik merupakan upaya yang mempunyai tujuan utama untuk
mencegah dan mengurangi penyebab langsung masalah gizi. Kegiatan ini pada
umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Contoh intervensi gizi spesifik antara lain
penerapan praktik gizi yang baik seperti pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif,
pemberian suplemen vitamin A, bubuk mikronutrien, zat besi, pengobatan malnutrisi,
maupun pencegahan penyakit infeksi melalui perilaku hidup bersih dan sehat.
Intervensi gizi sensitif merupakan upaya-upaya yang mempunyai tujuan utama
mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung, misalnya melalui
penyediaan akses air minum dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pertanian dan
ketahanan pangan, kesehatan, perawatan, pendidikan, keluarga berencana, dan
sebagainya.
Lancet series (2013) telah mengindentifikasi beberapa cara untuk memastikan bahwa
program intervensi gizi sensitif dapat lebih efektif dalam memberi kontribusi peningkatan
dampak gizi hingga 80%. Intervensi sensitif ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan,
termasuk melalui upaya-upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu
pendekatan untuk merubah perilaku masyarakat yang sudah terbukti efektif adalah
pendekatan STBM.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 17
POKOK BAHASAN 3: KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL STBM
Definisi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah
perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter
secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.
Kegiatan STBM dilakukan oleh masyarakat dengan berpedoman pada lima pilar STBM,
yaitu:
1. Stop buang air besar sembarangan;
2. Cuci tangan pakai sabun;
3. Mengelola air minum dan makanan rumah tangga;
4. Mengamankan sampah rumah tangga; dan
5. Mengamankan limbah cair rumah tangga.
Dalam menyelenggarakan STBM, masyarakat dipicu dan difasilitasi oleh tenaga
kesehatan, kader, pemerintah daerah, maupun fasilitator-fasilitator pemberdayaan
masyarakat lainnya untuk menemukan sendiri masalah kesehatan yang mereka anggap
penting dan kemudian memutuskan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat yang
akan mereka lakukan. Perubahan perilaku yang diharapkan di dalam STBM adalah
perubahan perilaku total, yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang tetapi dilakukan
oleh semua keluarga. Dengan adanya perubahan perilaku bersama diharapkan
masyarakat dapat memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.
STBM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.3/2014 tentang Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat, yang dilakukan melalui tiga strategi, yaitu:
a. Penciptaan lingkungan yang kondusif, melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan
kemitraaan berbagai pihak;
b. Peningkatan kebutuhan sanitasi, melalui perubahan perilaku masyarakat; dan
c. Peningkatan penyediaan akses sanitasi, melalui peningkatan akses terhadap produk
dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
Sebagai sebuah pendekatan untuk merubah perilaku masyarakat, pendekatan STBM
diharapkan dapat menjadi pintu masuk (entry point) untuk memicu perubahan perilaku
hidup bersih dan sehat secara luas, tidak hanya mencakup lima pilar STBM. Salah satu
perubahan perilaku yang diharapkan untuk dapat membantu tercapainya sasaran
prioritas pembangunan kesehatan, khususnya menurunkan stunting adalah perubahan
perilaku terkait gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Adapun tata kelola
kegiatan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kesehatan lingkungan, standar
baku mutu kesehatan lingkungan, dan pembagian peran dan tanggung jawab antara
pemerintah, masyarakat, maupun mitra lainnya diatur secara lebih spesifik dalam
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
VIII. REFERENSI
UU 36/2009 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
PERPRES no.2 th.2015 tentang RPJMN 2015-2019
Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi
Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 18
Pedoman Perencanaan Program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK)
Permenkes 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia
Sehat dengan pendekatan keluarga.
Permenkes No.3/2014 tentang STBM.
Maternal and Child Nutrition, The Lancet, 2013.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 19
MODUL MI.1
KONSEP DASAR STBM-STUNTING
I. DESKRIPSI SINGKAT
Modul Konsep Dasar STBM-Stunting ini disusun untuk membekali peserta agar
memahami stunting dan upaya pencegahannya, konsep dan stategi STBM, serta
integrasi kedua konsep ke dalam delapan pilar STBM-Stunting dan prinsip-prinsip
STBM-Stunting untuk melakukan perubahan perilaku secara berjenjang untuk
mencapai kondisi hygiene sanitasi dan pencegahan stunting yang lebih baik dan
berkelanjutan.
Indonesia merupakan negara terbesar kelima dengan jumlah anak stunting di dunia.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 mencatat ada sekitar 9 juta anak stunting
di Indonesia, meningkat dari 36,8% tahun 2007 ke 37,2% tahun 2013. Riskesdas
juga menunjukkan adanya kecenderungan provinsi yang memiliki akses sanitasi
yang kurang baik cenderung lebih banyak memiliki kasus stunting. Untuk mencegah
stunting, pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi
anak stunting. Terdapat dua model intervensi untuk mencegah stunting yaitu
intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik mencakup upaya-upaya mencegah
dan mengurangi gangguan secara langsung misalnya melalui imunisasi, pemberian
makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, dan pemantauan pertumbuhan.
Intervensi sensitif mencakup upaya-upaya mencegah dan mengurangi gangguan
secara tidak langsung misalnya melalui penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi,
peningkatan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesetaraan
gender. Di kabupaten Magetan, peningkatan akses sanitasi telah mengurangi
prevalensi stunting secara signifikan. Dalam lima tahun (2010-2014), akses jamban
di Magetan meningkat 40% dan dalam tiga tahun (2011-2014), kabupaten ini berhasil
mengurangi prevalensi stunting sebesar 7,3% menjadi 27,5%.
Konsep stunting dan konsep dasar STBM sangat penting disampaikan agar peserta
pelatihan bisa memahami secara utuh kedua konsep dan integrasinya, untuk
selanjutnya dapat memfasilitasi penerapan STBM-Stunting untuk meningkatkan
akses sanitasi dan mencegah serta menurunkan angka stunting di masyarakat.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami konsep dasar STBM
Stunting.
B. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:
1. Menjelaskan Stunting;
2. Menjelaskan Pencegahan Stunting;
3. Menjelaskan Konsep STBM;
4. Menjelaskan Prinsip-Prinsip STBM-Stunting;
5. Menjelaskan Strategi STBM-Stunting;
6. Menjelaskan Delapan Pilar STBM-Stunting;
7. Menjelaskan Tangga Perubahan Perilaku visi STBM-Stunting.
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai
berikut:
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 20
A. Pokok Bahasan 1: Stunting
a. Pengertian stunting
b. Penyebab stunting
c. Akibat stunting
B. Pokok Bahasan 2: Pencegahan Stunting
a. Pendekatan secara langsung/kegiatan gizi spesifik
b. Pendekatan secara tidak langsung
C. Pokok Bahasan 3: Konsep STBM
a. Pengertian STBM
b. Tujuan STBM
c. Sejarah program pembangunan sanitasi
D. Pokok Bahasan 4: Prinsip-Prinsip STBM-Stunting
a. Tanpa subsidi (untuk non kuratif)
b. Masyarakat sebagai pemimpin
c. Tidak menggurui/memaksa
d. Totalitas
E. Pokok Bahasan 5: Strategi STBM-Stunting
a. Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi-stunting
b. Peningkatan layanan penyediaan sanitasi dan pencegahan stunting
c. Penciptaan lingkungan yang kondusif
F. Pokok Bahasan 6: Delapan Pilar STBM-Stunting
a. Pengertian pilar-pilar dalam STBM-Stunting
b. Penyelenggaran pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting
c. Manfaat pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting
d. Tujuan Pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting
G. Pokok Bahasan 7: Tangga Perubahan Perilaku Visi STBM-Stunting
a. Tangga perubahan perilaku sanitasi
b. Tangga perubahan perilaku asupan gizi
c. Tangga perubahan perilaku visi STBM-Stunting
IV. METODE
Ceramah Tanya jawab, curah pendapat, diskusi kelompok, dan pemutaran film.
V. MEDIA DAN ALAT BANTU
Bahan tayang slide ppt, Film Dewi dan Putri, Film Stunting dan Masa Depan
Indonesia, LCD, komputer/laptop, kertas plano/flipchart, spidol, papan tulis, kain
tempel, lem semprot kain, meta plan, panduan pemutaran film, panduan diskusi
kelompok, serta modul.
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 6 jam pelajaran (T=3
JPL, P=3 JPL, dan PL=0 JPL) @45 menit. Untuk mempermudah proses
pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta, dilakukan langkah-
langkah kegiatan sebagai berikut:
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 21
Langkah 1. Pengkondisian (15 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Fasilitator menyampaikan salam dan menyapa peserta dengan ramah dan
hangat.
b. Fasilitator memperkenalkan diri.
c. Fasilitator memulai kegiatan dengan melakukan bina suasana di kelas.
2. Kegiatan Peserta
a. Mempersiapkan diri dan alat tulis bila diperlukan.
b. Menjawab salam.
c. Melakukan tugas yang diberikan.
Langkah 2. Pembahasan per Materi (255 menit)
Pokok Bahasan 1: Stunting (65 menit)
1. Kegiatan Fasilitator :
a. Fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat terkait dengan pengertian
stunting.
b. Peserta diajak diskusi kelompok, peserta dibagi menjadi 3 kelompok diskusi,
masing-masing kelompok membahas satu topik yaitu; 1) Tanda-tanda
stunting, 2) Penyebab Stunting, 3) Akibat Stunting. Diskusi dengan
menggunakan LP.1.1 Panduan Diskusi Kelompok Tanda-Tanda,
Penyebab, dan Akibat Stunting.
2. Kegiatan Peserta :
a. Menyampaikan pendapat
b. Mengikuti diskusi kelompok
c. Bertanya bila ada yang kurang jelas
d. Mencatat hal-hal yang diperlukan
Pokok Bahasan 2: Pencegahan Stunting (30 menit)
1. Kegiatan Fasilitator :
a. Fasilitator menyampaikan pembahasan berikutnya mengenai upaya
pencegahan stunting yang akan diawali dengan menonton film bersama.
b. Pemutaran “Film Dewi dan Putri” (LP.1.2 Panduan Pemutaran Film Dewi
dan Putri).
c. Fasilitator memimpin curah pendapat untuk mengidentifikasi pencegahan
stunting. Setiap peserta diminta menuliskan pendapatnya dalam kertas
metaplan.
d. Fasilitator merangkum hasil curah pendapat.
2. Kegiatan Peserta
a. Menonton film Dewi dan Putri.
b. Berpartisipasi aktif dalam memberikan pendapat.
c. Bertanya bila ada yang kurang jelas.
d. Mencatat hal-hal yang diperlukan.
Pokok Bahasan 3: Konsep STBM (60 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Fasilitator menanyakan kepada peserta, “siapa yang belum pernah
mendengar istilah STBM?”
b. Dilanjutkan dengan menanyakan, “siapa yang bisa menjelaskan pengertian
STBM?”
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 22
c. Kemudian fasilitator menanyakan kembali pada peserta, “apa tujuan STBM?”
d. Fasilitator menegaskan kembali hasil curah pendapat terkait pengertian
STBM dan tujuan STBM.
e. Fasilitator mengajak peserta melakukan diskusi kelompok terkait Sejarah
pembangunan sanitasi dengan menggunakan LP.1.3 Panduan Diskusi
Kelompok Sejarah Program Pembangunan Sanitasi.
f. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah sudah paham dan
memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya/klarifikasi.
g. Fasilitator menjawab/menjelaskan sesuai yang ditanyakan peserta.
2. Kegiatan Peserta
a. Menyampaikan pendapat.
b. Menjawab pertanyaan.
c. Mengikuti diskusi kelompok.
d. Bertanya bila ada yang kurang jelas.
e. Mencatat hal-hal yang diperlukan.
Pokok Bahasan 4 : Prinsip-Prinsip STBM-Stunting (15 menit)
1. Kegiatan Fasilitator :
a. Fasilitator mengajak peserta untuk mengingat kembali hasil diskusi terkait
dengan sejarah pembangunan sanitasi.
b. Dengan menggunakan hasil diskusi pada PB.3 (LP 1.3) lakukan
pendalaman lebih lanjut melalui curah pendapat dengan menanyakan:
a. Apa keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan/proyek?
b. Berapa lama waktu yang ditargetkan dengan perubahan yang
diharapkan?
c. Bagaimana keberlanjutan penggunaan sarana (apakah masih dipakai,
mengapa masih dipakai/tidak dipakai, siapa saja yang terlibat dan
keterlibatan dalam hal apa)?
d. Apakah terjadi pemutusan alur penularan penyakit di komunitas?
e. Apakah ada risiko penularan penyakit di masyarakat?
f. Bagaimana kesimpulan keberhasilan kegiatan/proyek jika
dibandingkan dengan tujuan kegiatan untuk memutus alur penularan
penyakit di komunitas? Apakah berhasil atau tidak berhasil/gagal?
c. Tanyakan kepada peserta, “pembelajaran apa yang bisa dipetik dari
pengalaman kegiatan/proyek pembangunan sanitasi masa lalu?” Tandai hal-
hal yang menjadi ciri-ciri kegiatan/proyek (dana, penyuluhan, yang
terlibat/penerima manfaat/proyek, yang memimpin kegiatan/proyek, dan
sebagainya).
d. Fasilitator menegaskan kegagalan pendekatan masa lalu dengan menyebut
kembali ciri-ciri kegagalan kegiatan/proyek pembangunan sanitasi masa lalu.
e. Tanyakan kepada peserta, “jika kita ingin berhasil, apakah kegagalan tersebut
akan dilakukan pada masa yang akan datang?”
f. Tanyakan kepada peserta, “apa yang seharusnya dilakukan/dipegang teguh
dan menjadi prinsip agar kegiatan pembangunan sanitasi berhasil?”
g. Fasilitator menegaskan kembali hasil curah pendapat bahwa dalam
implementasi pendekatan STBM ada prinsip yang harus dipegang teguh,
yaitu: non subsidi, tidak mengurui, masyarakat sebagai pemimpin, dan
totalitas.
h. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan curah pendapat, dengan
menanyakan, “apakah prinsip-prinsip STBM dapat diterapkan dalam upaya
mencegah stunting?”
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 23
i. Fasilitator menegaskan kembali hasil curah pendapat tentang prinsip-prinsip
STBM-stunting, yaitu a) tanpa subsidi, untuk non kuratif, b) masyarakat
sebagai pemimpin, c) tidak menggurui/memaksa, dan d) totalitas.
j. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah sudah paham dan
memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya/klarifikasi.
k. Fasilitator menjawab/menjelaskan sesuai yang ditanyakan peserta.
2. Kegiatan Peserta
a. Menyampaikan pendapat
b. Menjawab pertanyaan
c. Bertanya bila ada yang belum jelas
d. Mencatat hal-hal yang diperlukan
Pokok Bahasan 5 : Strategi STBM-Stunting (30 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Fasilitator menanyakan kepada peserta, kegiatan yang sudah dilakukan
untuk mencegah stunting? Kemudian peserta diminta menuliskan jawaban
pada kertas metaplan dengan huruf cetak/besar. Satu lembar kertas untuk
satu kegiatan, masing-masing peserta boleh menulis lebih dari satu kegiatan.
b. Lakukan hal yang sama untuk implementasi STBM.
c. Sementara peserta menulis pada kertas metaplan, fasilitator menempelkan
kertas yang bertuliskan “Demand”, “Supply”, “Enabling” pada kain rekat
dengan jarak diatur membentuk segi tiga.
ENABLING
DEMAND SUPPLY
d. Kemudian fasilitator menjelaskan maksud 3 tulisan tersebut.
e. Minta kepada peserta untuk menempelkan tulisan tentang kegiatan yang
sudah dilakukan terkait upaya pencegahan stunting dan implementasi STBM
pada posisi mana, apakah termasuk “Demand”, “Supply”, atau “Enabling”.
f. Tanyakan kepada peserta, “jika ingin mencapai sukses untuk pencegahan
stunting dan implementasi STBM, apakah kegiatan-kegiatan hanya dilakukan
pada salah satu “Demand” , “Supply”, “Enabling” saja?”
g. Dilanjutkan dengan pertanyaan, “apakah masing-masing
komponen“Demand”, “Supply”, “Enabling” saling mempengaruhi?” Setelah
dijawab oleh peserta, hubungkan tulisan Demand-Supply-Enabling dengan
garis sehingga membentuk segi tiga.
h. Fasilitator menegaskan, bahwa jika progam pendekatan STBM-Stunting ingin
sukses maka ada 3 komponen strategi yang harus dilakukan secara
terintegrasi yaitu mewujudkan “Demand-Supply-Enabling”.
i. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah sudah paham dan
memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya/klarifikasi.
j. Fasilitator menjawab/menjelaskan sesuai yang ditanyakan peserta
2. Kegiatan Peserta
a. Menyampaikan pendapat
b. Menjawab pertanyaan
c. Bertanya bila ada yang kurang jelas
d. Mencatat hal-hal yang diperlukan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 24
Pokok Bahasan 6 : Delapan Pilar STBM-Stunting (30 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Fasilitator menggali pengetahuan peserta tentang 5 pilar STBM dan mengapa
harus dengan 5 pilar.
b. Fasilitator menggali pengetahuan peserta tentang sasaran 1000 hari pertama
kehidupan (ibu hamil, bayi, baduta) dalam pencegahan stunting, dan
mengapa difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan.
c. Apa yang harus diperhatikan pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan
dalam pencegahan tersebut (gizi ibu hamil, pemantauan pertumbuhan, dan
pemberian makan bayi dan anak)
d. Fasilitator merangkum dan menegaskan hasil curah pendapat bahwa ada 8
pilar dalam STBM-Stunting.
e. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah sudah paham dan
memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya/klarifikasi.
f. Fasilitator menjawab/menjelaskan sesuai yang ditanyakan peserta
2. Kegiatan Peserta
a. Menyampaikan pendapat.
b. Menjawab pertanyaan.
c. Bertanya bila ada yang kurang jelas.
d. Mencatat hal-hal yang diperlukan.
Pokok Bahasan 7 : Tangga Perubahan Perilaku Visi STBM-Stunting (15 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Fasilitator menggali pemahaman peserta tentang perubahan perilaku,
bagaimana perubahan perilaku bisa terjadi pada seseorang (tidak tahu, tahu,
mau, melakukan).
b. Fasilitator menegaskan kembali hasil curah pendapat tentang tangga
perubahan perilaku. Seseorang tidak melakukan perilaku baru karena tidak
tahu, namun setelah mendapat informasi, orang tersebut menjadi tahu,
kemudian membuat pertimbangan dan memutuskan mencoba perilaku baru.
Setelah merasakan manfaat dan dorongan serta dukungan dari lingkungan
maka perilaku baru tersebut akan menjadi kebiasaan/perilaku permanen.
c. Fasilitator menanyakan kepada peserta, “apa yang diperlukan agar perilaku
baru dapat terjadi?” Fasilitator dapat mencontohkan salah satu pilar STBM-
Stunting dengan menanyakan, misalnya: “apa yang diperlukan seseorang
untuk terbiasa melakukan cuci tangan pakai sabun? Tegaskan bahwa
perilaku terjadi karena adanya sarana.
d. Fasilitator menayangkan gambar Tangga Perubahan Perilaku Visi STBM-
Stunting dan menjelaskan bahwa perubahan perilaku perlu dilakukan secara
bertahap yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan
di masyarakat. Perubahan perilaku tidak hanya membutuhkan sarana/fasilitas
fisik tetapi juga kelembagaan dan kebijakan di masyarakat seperti adanya
komite STBM-stunting, kegiatan-kegiatan posyandu, aturan dan mekasnisme
untuk mempertahankan perilaku baru, dan sebagainya. Perubahan perilaku
baru dilakukan secara bertahap hingga mencapai 8 pilar STBM-Stunting yang
didukung dengan sarana/fasilitasi yang semakin meningkat kualitasnya.
e. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah sudah paham dan
memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya/klarifikasi.
f. Fasilitator menjawab/menjelaskan sesuai yang ditanyakan peserta.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 25
2. Kegiatan Peserta
a. Menyampaikan pendapat.
b. Menjawab pertanyaan.
c. Bertanya bila ada yang belum jelas.
d. Mencatat hal-hal yang diperlukan.
Langkah 3. Rangkuman (10 Menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Fasilitator memberikan pertanyaan terkait dengan materi untuk mengetahui
tingkat pemahaman peserta (3 menit).
b. Fasilitator mengajak peserta untuk menonton film “Stunting dan Masa
Depan Indonesia” untuk menyimpulkan sesi MI.1 (4 menit).
c. Fasilitator merangkum hasil pembelajaran (2 menit).
d. Fasilitator menutup pertemuan dengan menyampaikan salam (1 menit).
2. Kegiatan Peserta.
a. Mencatat hal-hal yang penting.
b. Membalas salam.
VII. URAIAN MATERI
POKOK BAHASAN 1: STUNTING
A. Pengertian Stunting
Stunting adalah kondisi panjang/tinggi badan anak dibawah standar usia anak. Secara
fisik balita stunting lebih pendek dibandingkan balita normal lainnya yang seumur.
Stunting merupakan akibat dari kekurangan gizi jangka panjang karena kurangnya
asupan dan infeksi penyakit berulang. Anak stunting cenderung berisiko lebih besar
menderita penyakit atau mudah sakit, mengalami hambatan perkembangan mental,
mengalami gangguan kecerdasan, memiliki prestasi sekolah yang rendah, dan berisiko
lebih besar terhadap kematian (WHO, 2005).
Tanda-tanda stunting: Bagaimana mengetahui anak stunting?
Stunting dapat diketahui melalui pengukuran antropometri dengan kondisi panjang/
tinggi badan menurut umur anak berada di bawah -2 Standar Deviasi ( < -2,0 SD) dari
populasi rujukan WHO (Permenkes No.1995 Tahun 2010 tentang Standar Antropometri
Penilaian Status Gizi Anak). Anak terlihat normal (tidak cacat, tidak cebol, tidak kuntet),
namun lebih pendek dari anak seusianya.
Gambar 4. Anak Stunting
Sumber: http://elearning.stbm-indonesia.org/home/index/
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 26
B. Penyebab Stunting
Stunting sebagai suatu masalah gizi di Indonesia disebabkan beberapa faktor baik
secara langsung maupun tidak langsung:
a. Penyebab langsung
Stunting secara langsung dipengaruhi oleh asupan makan dan penyakit infeksi.
Kedua faktor ini saling berpengaruh satu sama lain. Kurangnya asupan makan, baik
jumlah maupun kualitas secara terus menerus akan menyebabkan anak mudah
terkena penyakit infeksi dan menghambat pertumbuhan anak. Sebaliknya anak yang
terus menerus sakit akan malas makan sehingga asupan makanan yang dia
dapatkan tidak cukup. Akibanya, anak dapat menjadi stunting. Sebagai contoh,
penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dapat
mempengaruhi asupan makan anak sehingga dapat mengakibatkan gangguan
pertumbuhan, yang kemudian dapat menyebabkan anak stunting.
b. Penyebab tidak langsung
Stunting juga dipengaruhi oleh aksesibilitas pangan, pola asuh, ketersediaan air
minum/sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Aksesibilitas pangan yang mudah dan
dengan harga yang terjangkau akan memudahkan keluarga mengonsumsi makanan
yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Selain itu konsumsi makanan juga
dipengaruhi oleh pengetahuan keluarga dalam memilih bahan makanan yang dibeli
dan mengolahnya secara aman dan sehat. Pola asuh, misalnya pemberian makan
bayi dan anak (PMBA) juga mempengaruhi status gizi anak. Ketersediaan air minum
dan sanitasi yang aman dan layak juga sangat berpengaruh pada status gizi dan
kesehatan ibu hamil dan anak, terutama dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS). Kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, juga
turut menentukan status gizi ibu hamil dan anak.
Dari faktor penyebab langsung dan tidak langsung di atas, diketahui bahwa akar masalah
status gizi tidak sepenuhnya masalah kesehatan tetapi menyangkut masalah-masalah di
luar kesehatan seperti kelembagaan, politik dan idelogi, kebijakan ekonomi, sumber
daya, lingkungan, teknologi, dan kependudukan. Oleh karena itu untuk melakukan
perbaikan gizi, maka sektor yang terkait dengan akar masalah gizi ini perlu dilibatkan.
Secara lengkap penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 5. Kerangka Pikir Penyebab Masalah Kesehatan Gizi
Sumber: World Bank 2011, diadaptasi dari UNICEF 1990 & Ruel 2008
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 27
Bila dikaji lebih dalam dengan berfokus pada sanitasi dan gizi, terdapat keterkaitan yang
sangat erat antara kemiskinan, akses air minum dan sanitasi, dan kejadian stunting
sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:
Diare
jamban Kontaminasi
Kotoran,
tangan, tanah, Infeksi
Pe
air dan usus
nye Kotoran
makanan
dia- hewan
an
Protozoa /
Pengelolaan kecacingan anemia
Air Stunting
septic tank
min
um
Kemi sk I nan
dan
sani
tasi Sumber air bersih Air
tergenang malaria
ya
ng
ti
dak waktu Pola asuh
la
yak
Ketersediaan Akses Produksi Asupan
air bersih makanan RT makan
air bersih
Penggunaan
air
Gambar 6. Alur Hubungan Hygiene-Sanitasi dan Gizi
Sumber:Chase, C and Ngure, F, 2016
Terdapat enam alur terjadinya stunting dengan berakar pada isu kemiskinan, akses air
minum, dan sanitasi. Untuk mencegah terjadinya stunting, dapat dilakukan dengan
memutus alur berikut:
Alur 1: Pencegahan stunting melalui penurunan kejadian diare dengan
mengurangi kontaminasi kotoran di lingkungan;
Alur 2: Pencegahan stunting melalui penurunan kejadian infeksi usus dengan
mengurangi kontaminasi kotoran di lingkungan;
Alur 3: Pencegahan stunting dengan mengurangi paparan dan infeksi protozoa
dan cacing melalui perbaikan higiene dan sanitasi;
Alur 4: Pencegahan stunting melalui penurunan kejadian anemia dengan
perbaikan higiene dan sanitasi;
Alur 5: Pencegahan stunting dengan mengurangi pemborosan waktu untuk
mencari air bersih dan menjaga anak yang sakit serta waktu dan biaya untuk
mencari pengobatan;
Alur 6: Hubungan langsung higiene dan sanitasi dengan kekurangan gizi
(termasuk stunting).
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 28
Faktor Risiko Stunting
Faktor risiko stunting dapat dikategorikan ke dalam beberapa kondisi yakni keadaan
ibu/wanita usia subur, keadaan bayi, dan keadaan lingkungan. Kondisi tersebut secara
singkat dijelaskan sebagai berikut:
a. Ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK) dan menderita anemia
Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) adalah ibu hamil dengan kondisi kekurangan
gizi akibat kurangnya asupan makanan sumber energi dalam waktu yang cukup
lama. Ibu hamil dengan kondisi KEK dan atau dengan anemia yang diketahui dari
hasil penapisan (screening) ibu hamil, berisiko melahirkan bayi pendek dan Berat
Badan Lahir Rendah (BBLR). Kondisi ini berisiko terhadap bayi yang akan
dilahirkannya seperti kematian, kurang gizi, gangguan pertumbuhan, dan gangguan
perkembangan anak yang dapat menyebabkan anak menjadi pendek atau stunting.
b. Bayi yang tidak mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif telah terbukti sebagai satu-satunya makanan terbaik
untuk bayi usia 0-6 bulan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Bila
bayi tidak mendapat ASI Eksklusif, maka akan meningkatkan risiko terhadap penyakit
infeksi yang diakibatkan oleh pemberian makanan atau minuman lain yang terlalu
dini sehingga pertumbuhannya menjadi terganggu. Penyakit yang berulang diderita
oleh anak dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting.
c. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tidak tepat.
Setelah usia 6 bulan, kualitas ASI tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan gizi bayi
sehingga bayi perlu diberi makanan pendamping ASI (MP-ASI) sambil tetap diberikan
ASI hingga berusia 2 tahun. Tantangan yang dihadapi pada masa pemberian MP-ASI
adalah bagaimana ibu/pengasuh memiliki pengetahuan dan perilaku yang benar
sehingga dapat mempraktikkan pemberian MP-ASI secara tepat. Bila MP-ASI yang
diberikan kurang baik secara kuantitas dan kualitas, maka asupan makan anak tidak
dapat memenuhi kebutuhan gizinya sehingga anak lebih mudah terkena penyakit
infeksi akibat daya tahan tubuh yang lemah. Bila hal ini terjadi secara terus-menerus
maka risiko anak menderita stunting akan menjadi lebih tinggi karena gangguan
pertumbuhan pada anak.
d. Pertumbuhan yang tidak dipantau
Pemantauan pertumbuhan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan
stunting. Apabila pertumbuhan anak dipantau secara rutin, maka akan dapat segera
terdeteksi bila terjadi gangguan pertumbuhan untuk segera ditangani. Bila
pertumbuhan anak tidak dipantau, maka tidak dapat diketahui status
pertumbuhannya, adakah masalah atau gangguan pertumbuhan yang dialami,
sehingga seringkali anak terlanjur jatuh pada masalah gizi yang berat, salah satunya
stunting.
e. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang tidak layak
Sebuah studi terkini di Indonesia menemukan bahwa kombinasi antara sanitasi yang
tidak layak dan kualitas air minum yang tidak aman merupakan faktor risiko stunting
(Torlesse, et.al., 2016). Sebuah analisis penilaian risiko komparatif global terbaru dari
137 data negara berkembang mengidentifikasi faktor-faktor risiko lingkungan (yaitu,
kualitas air yang buruk, kondisi sanitasi yang buruk, dan penggunaan bahan bakar
padat) memiliki pengaruh terbesar kedua pada kejadian stunting secara global
(Andrews, et.al. 2016).
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 29
C. Akibat Stunting
Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang bekaitan dengan gangguan
pertumbuhan anak yang berakibat pada penuruan kualitas dan kapasitas sumber daya
manusia. Secara singkat, akibat stunting adalah sebagai berikut:
a. Gangguan pertumbuhan sejak dalam kandungan akan berakibat secara fisik, mental,
dan intelektual pada bayi yang dilahirkan.
b. Anak perempuan yang stunting kelak berisiko melahirkan bayi BBLR dan juga
stunting.
c. Stunting menghambat perkembangan kognitif, nilai sekolah, dan keberhasilan
pendidikan anak.
d. Stunting kelak menurunkan produktivitas anak pada usia dewasa.
e. Stunting pada anak telah terbukti berkorelasi bermakna dengan kejadian penyakit
tidak menular (PTM) saat dewasa.
Hal yang paling dikhawatirkan dari stunting adalah lahirnya generasi penerus bangsa
yang lemah, yang mudah sakit, dan tidak memiliki kapasitas kecerdasan dan
kemampuan untuk berdaya di masyarakat.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, stunting disebakan oleh brbagai faktor. Oleh
karena itu, pencegahan dan penanganannya memerlukan kerjasama semua pemangku
kepentingan. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan upaya
penanggulangan stunting melalui pendekatan sanitasi dan gizi.
POKOK BAHASAN 2 : PENCEGAHAN STUNTING
Berdasarkan faktor penyebabnya, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan dua
pendekatan yaitu secara langsung melalui kegiatan gizi spesifik dan secara tidak
langsung melalui kegiatan gizi sensitif.
A. Pendekatan secara langsung/intervensi gizi spesifik.
Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, antara lain berupa:
a. Pada ibu hamil
Memperbaiki gizi dan kesehatan Ibu hamil merupakan cara terbaik dalam
mengatasi stunting. Ibu hamil perlu mendapat makanan yang baik, sehingga
apabila ibu hamil dalam keadaan sangat kurus atau mengalami Kurang Energi
Kronis (KEK), maka perlu diberikan makanan tambahan kepada ibu hamil
tersebut.
Ibu hamil normal harus memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan minimal
4 kali selama kehamilan.
Setiap ibu hamil perlu mendapat tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama
kehamilan.
Kesehatan ibu harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit.
b. Pada bayi baru lahir
Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan begitu bayi lahir
melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
Ibu mendapat 2 kapsul vitamin A merah di masa nifas.
Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi Air Susu Ibu (ASI) saja atau ASI
Eksklusif.
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan di posyandu.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 30
c. Bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun
Mulai usia 6 bulan, selain ASI bayi diberi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).
Pemberian ASI terus dilakukan sampai bayi berumur 2 tahun.
Bayi dan anak memperoleh kapsul vitamin A, taburia, imunisasi dasar lengkap.
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan di posyandu.
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap rumah
tangga.
B. Pendekatan secara tidak langsung/intervensi gizi sensitif.
Intervensi gizi sensitif melibatkan sektor pembangunan lain seperti: penanggulangan
kemiskinan, ketahanan pangan dan gizi, penyediaan lapangan kerja, pendidikan anak
usia dini (PAUD), program Keluarga Berencana (KB), Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), perbaikan infrastruktur (perbaikan jalan, pasar), dan penyediaan air bersih serta
perbaikan perilaku higienis dan saniter.
Untuk mengatasi dan mencegah stunting, diperlukan kolaborasi antara sektor-sektor
yang terlibat seperti kesehatan untuk air minum dan sanitasi, pendidikan, infrastruktur,
dan lain sebagainya. Kolaborasi dan integrasi program/intervensi-intervensi ini
diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan
cerdas.
Salah satu cara untuk mencegah penyebab stunting secara tidak langsung adalah
dengan memutus rantai penularan penyakit atau alur kontaminasi dan melakukan
perubahan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan dengan pendekatan STBM.
Secara sederhana, upaya untuk memutus alur penularan penyakit diare dan stunting
terlihat pada gambar-7. Adapun kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi secara terpadu yang
dapat dilakukan agar gizi dan perkembangan janin dapat optimal terlihat pada gambar 8.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 31
Gambar 7. Diagram Pemutusan Mata Rantai Penularan Diare untuk Mencegah Stunting
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 32
Manfaat Seumur Hidup
Angka Kesakitan dan Perkembangan Kogrnitif, Prestasi di Sekolah dan Tingi badan dewasa, Kapasitas Kerja
kematian Anak Motorik, dan Sosial Emosi Kemampuan Belajar Obesitas, dan NCD dan Produktivitas
Intervensi dan program gizi spesifik Program dan Pendekatan Gizi sensitif
Kesehatan remaja dan gizi pada Gizi dan Perkembangan Janin dan Anak Secara Optimal
Pertanian dan ketahanan pangan
masa prakonsepsi Jaring Pengaman Sosial
Pemberian suplemen makanan Bebas penyakit Tumbuh kembang anak usia dini
kepada ibu hamil/menyusui ASI, makanan kaya Praktik pemberian
menular yang Kesehatan mental ibu
Suplemen atau fortifikasi gizi dan rutinitas makan dan perawatan,
makan pengarahan, stimulasi rendah Pemberdayaan perempuan
mikronutrien Perlindungan anak
ASI dan makanan pemdamping Pendidikan dalam kelas
Pemberian suplemen makanan Air minum dan sanitasi
kepada anak-anak Layanan kesehatan dan KB
Diversifikasi makanan Akses dan
Ketahanan pangan, Sumber daya
Perilaku dan stimulasi pemanfaatan
termasuk pemberian makanan
pemberian makanan layanan kesehatan,
ketersediaan akses dan perawatan (ibu, Pengembangan Lingkungan
Pengobatan malnutrisi akut lingkungan yang
yang ekonomis dan rumah tangga, dan Pendukung
berat aman dan sehat.
pemanfaatan masyarakat) Evaluasi yang seksanma
Pencegahan dan
makanan Strategi advokasi
penanggulangan penyakit
Intervensi gizi dalam keadaan Koordinasi secara horizontal dan
darurat Pengetahuan dan Bukti vertical
Politik dan tata kelola Akuntabilitas, insentif, peraturan
Kepemimpinan, kapasitas, dan sumber daya keuanga perundang-undangan
Konteks sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup Program kepemimpinan
(nasional dan global) Inovasi di bidang peningkatan
kapasitas
Mobilisasi sumber daya domestik
Gambar 8. Aksi-Aksi Agar Gizi dan Perkembangan Janin dan Anak Optimal
Sumber: Black, et.al. Lancet, 2012.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 33
POKOK BAHASAN 3: KONSEP STBM
A. Pengertian STBM
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk
merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara
pemicuan.
Penyelenggara STBM adalah masyarakat, baik yang terdiri dari individu, rumah tangga,
maupun kelompok-kelompok masyarakat. Untuk memahami STBM maka pengertian-
pengertian berikut perlu diketahui, yaitu:
1. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan saniter
individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola
pikir, perilaku, dan kebiasaan indivudu atau masyarakat.
2. Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah desa/kelurahan intervensi
pendekatan STBM dan dijadikan target antara karena untuk mencapai kondisi
sanitasi total dibutuhkan pencapaian kelima pilar STBM. Ada 3 indikator
desa/kelurahan yang melaksanakan STBM: (i) minimal telah ada intervensi melalui
pemicuan di salah satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut; (ii) ada masyarakat
yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM seperti disebutkan
pada poin pertama, baik individu (natural leader) ataupun bentuk komite; (iii) sebagai
respon dari aksi intervensi STBM, kelompok masyarakat menyusun suatu rencana
aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar-pilar
STBM, yang telah disepakati bersama; misal: mencapai status ODF (Open
Defecation Free)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
3. Desa/Kelurahan ODF/SBS adalah desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya telah
buang air besar di jamban sehat.
4. Desa STBM, adalah desa yang telah mencapai 5 (lima) pilar STBM atau kondisi
sanitasi total.
B. Tujuan STBM
Tujuan penyelenggaraan STBM untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis
dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya.
C. Sejarah Program Pembangunan Sanitasi
Jauh sebelum Indonesia merdeka, program sanitasi sudah dilakukan oleh masyarakat
Indonesia.Tahun 1930, mantri higiene Belanda, Dr. Heydrick melakukan kampanye untuk
BAB di kakus. Dr. Heydrick sendiri dikenal sebagai mantri kakus. Di tahun 1936,
didirikanlah sekolah mantri higiene di Banyumas yaitu yang kemudian dikenal dengan
Sekolah Pembantu Penilik Higiene (SPPH). Siswa mendapatkan pendidikan 18 bulan
sebelum mereka diterjunkan ke kampung-kampung untuk mempromosikan hidup sehat
dan melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit. Untuk mendapatkan sumber daya
manusia dalam melaksanakan program-program tersebut, Kementerian Kesehatan
mendirikan sekolah-sekolah kesehatan lingkungan, yang sekarang dikenal dengan nama
Politeknik Kesehatan (Poltekes) Jurusan Kesehatan Lingkungan.
Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 5 tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan
Sarana Kesehatan yang memerintahkan dibangunnya gedung Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas), sarana penyediaan air minum pedesaan, dan tempat
pembuangan kotoran (jamban keluarga). Program pembangunan tentang sarana air
minum dan jamban keluarga dikenal dengan singkatan “SAMIJAGA”. Tujuan Inpres
tersebut adalah memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat
mungkin kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan perkotaan
berpenghasilan rendah, serta meningkatkan realisasi derajat kesehatan rakyat terutama
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 34
dengan mewujudkan keadaan higiene dan sanitasi masyarakat pedesaan yang lebih
baik.
Pada tahap awal disediakan 10.500 unit sarana air minum dan 150.000 unit jamban
keluarga. Pembagian per provinsi berdasarkan kejadian wabah kolera dan penyakit perut
lainnya, daerah sulir air bersih, tersedianya tenaga higiene sanitasi, dan tersedianya hasil
survei pendahuluan. Bantuan sarana air minum dalam bentuk salah satu jenis berikut ini;
penampungan mata air dengan perpipaannya, penampungan air hujan, perlindungan
mata air, sumur artesis, dan sumur dengan pompa tangan. Bantuan sarana pembuangan
kotoran manusia dalam bentuk jamban keluarga. Semua jenis teknologi sarana air minum
dan jamban keluarga sudah ditentukan desain teknisnya. Penentuan lokasi sarana air
minum dan jamban keluarga ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usulan Kepala
Dinas Kesehatan.
Periode 1970-1997, pemerintah melakukan beragam program pembangunan sanitasi.
Program-program tersebut umumnya dilakukan dengan pendekatan keproyekan,
sehingga faktor keberlanjutannya sangat rendah. Hal ini secara tidak langsung
menyebabkan rendahnya peningkatan akses sanitasi masyarakat.
Hasil studi Indonesian Sanitation Sector Development Program (ISSDP) mencatat hanya
53% dari masyarakat Indonesia yang BAB di jamban yang layak pada tahun 2007,
sedangkan sisanya BAB di sembarang tempat. Lebih jauh hal ini berkorelasi dengan
tingginya angka diare dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak
bersih.
Pembangunan sanitasi di Indonesia sebelum lahirnya STBM tahun 2008 pada umumnya
dilakukan dengan pendekatan proyek dimana masyarakat sebagai sasaran program
kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan
maupun monitoring dan evaluasi. Masyarakat hanya menerima walaupun sarana yang
dibangun tidak tanggap terhadap kebutuhan mereka.
Desain proyek yang demikian mengakibatkan tidak terjaminnya keberlanjutan sarana.
Sarana kurang dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat karena mereka kurang
merasa memiliki. Banyak sarana tidak berfungsi. Akibatnya kondisi sanitasi tetap buruk
sehingga dampak yang diharapkan yaitu menurunnya kejadian penyakit berbasis air dan
sanitasi seperti diare tidak tercapai. Diare tetap menjadi kelompok penyakit terbesar di
Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pembangunan sanitasi dengan pendekatan yang
lebih baik yaitu mengedepankan peran aktif dan partisipasi masyarakat.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan keberlanjutan program dan tingkat keberhasilan
yang ingin dicapai, pemerintah melakukan perubahan pendekatan pembangunan
sanitasi, dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2008, pemerintah
mencanangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Secara ringkas, perbedaan pendekatan pembangunan sanitasi masa lalu dan saat ini
terlihat dari ciri-ciri sebagai berikut:
Tabel 1. Kecenderungan Pelaksanaan Program Air dan Sanitasi di Indonesia
Program-program terdahulu Kecenderungan saat ini
(biasanya Target Oriented)
Keberhasilan dilihat dari Keberhasilan dilihat dari perubahan perilaku
perkembangan jumlah sarana dan kesehatan
Adanya subsidi Munculnya solidaritas sosial
Model-model sarana disarankan oleh Model-model sarana digagas dan
pihak luar dikembangkan oleh masyarakat
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 35
Program-program terdahulu Kecenderungan saat ini
(biasanya Target Oriented)
Sasaran utama adalah kepala Sasaran utama adalah masyarakat desa
keluarga secara utuh
Top down (dari atas ke bawah) Bottom up (dari bawah ke atas)
Fokus pada: jumlah sarana sanitasi Fokus pada: perubahan perilaku dengan
menggunakan serta memelihara sarana
yang dibangun
Pendekatannya bersifat “blue print” Pendekatannya lebih fleksibel.
Konsep STBM diadopsi dari konsep Community Led Total Sanitation (CLTS) yang telah
disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan di Indonesia. CLTS adalah sebuah
pendekatan dalam pembangunan sanitasi pedesaan dan mulai berkembang pada tahun
2001. Pendekatan ini awalnya diujicobakan di beberapa komunitas di Bangladesh dan
saat ini sudah diadopsi secara massal di 60 negara
(http://www.communityledtotalsanitation.org).
Pendekatan ini berawal dari penilaian dampak partisipatif program air bersih dan sanitasi
yang dijalankan oleh Water Aid selama 10 tahun. Salah satu rekomendasi dari penilaian
tersebut adalah perlunya mengembangkan sebuah strategi untuk secara perlahan-lahan
mencabut subsidi pembangunan toilet. Ciri utama pendekatan CLTS adalah tidak
adanya subsidi terhadap infrastruktur (jamban keluarga) dan tidak menetapkan model
standar jamban yang nantinya akan dibangun oleh masyarakat.
Pada dasarnya CLTS adalah “pemberdayaan” dan “tidak membicarakan masalah
subsidi”. Artinya, masyarakat yang menentukan sendiri jenis sarana sanitasi yang akan
dibangun dan dimiliki sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka sendiri.
Pendekatan Community lead tidak hanya diterapkan dalam sektor sanitasi, tetapi juga
dapat digunakan dalam sektor lain seperti pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Prinsip
yang terpenting adalah:
1. Inisiatif masyarakat;
2. Total atau keseluruhan, keputusan masyarakat dan pelaksanaan secara kolektif
adalah kunci utama;
3. Solidaritas masyarakat (laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin) sangat terlihat
dalam pendekatan ini;
4. Semua dibuat oleh masyarakat, tidak ada ikut campur pihak luar, dan biasanya akan
muncul “natural leader”.
POKOK BAHASAN 4: PRINSIP-PRINSIP STBM-STUNTING
Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pendekatan STBM-Stunting diambil dari pengalaman
implementasi program pembangunan air minum dan sanitasi di masa lalu yang boleh
dikatakan mengalami kegagalan. Pelajaran besar yang sangat berharga yang dapat
dipetik yaitu:
1. Dana yang diberikan oleh pemerintah maupun LSM untuk membantu masyarakat
membangun sarana sanitasi tidak mencukupi untuk semua masyarakat, sehingga
hanya keluarga tertentu saja yang menjadi sasaran untuk menerima bantuan
tersebut. Hal tersebut menyebabkan keluarga yang tidak menerima bantuan
merasa iri dan menunggu bantuan tahap berikutnya, sehingga perilaku tidak sehat
tetap berlangsung dan risiko penyakit tetap mengancam masyarakat. Pemberian
bantuan kepada masyarakat menyebabkan ketergantungan masyarakat kepada
pemerintah sehingga bila tidak ada bantuan masyarakat tidak mau bergerak atau
berubah walaupun kondisi tersebut tidak sehat bagi masyarakat.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 36
2. Program sanitasi yang lalu merupakan paket yang sudah ditentukan dari
pemerintah atau pemberi bantuan (donor), dimana desain proyek dan pilihan
teknologi sudah ditetapkan, sehingga masyarakat hanya sebagai obyek yang tidak
punya kuasa untuk memutuskan. Teknologi yang disediakan sering tidak tanggap
terhadap kebutuhan masyarakat, baik dipandang dari segi budaya, lokasi,
lingkungan, ekonomi maupun kemampuan teknis opersional serta pemeliharaan.
Masyarakat merasa tidak cocok dengan teknologi tersebut sehingga sarana yang
dibangun tidak dipakai atau tidak dipelihara.
3. Program sanitasi terdahulu kurang memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam
memutuskan untuk menentukan pilihan teknologi, perencanaan, pelaksanaan
pembangunan maupun dalam monitoring dan evaluasi. Semua sudah diputuskan
dari atas dan masyarakat hanya menerima saja. Kurang terlibatnya masyarakat
menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap sarana yang dibangun, sehingga
masyarakat merasa itu bangunan milik pemerintah atau pihak lain, akibatnya saat
ada kerusakan maka masyarakat menunggu bantuan dari pemiliknya yaitu
pemerintah atau pihak donor untuk memperbaikinya.
4. Evaluasi terhadap keberhasilan program sanitasi masa lalu difokuskan pada jumlah
sarana yang telah dibangun, jadi bila target jumlah sarana yang telah dibangun
telah dicapai maka program tersebut dikatakan berhasil. Namun tidak
memperhatikan apakah sarana sanitasi yang dibangun digunakan atau tidak oleh
masyarakat, dipelihara atau tidak.
5. Program sanitasi masa lalu sifatnya top-down, apa yang sudah ditetapkan dari atas
harus dilaksanakan di lapangan, pendekatannya kaku tidak fleksibel.
6. Seiring dengan perjalanan waktu setelah bantuan pembangunan Samijaga untuk
tahap-tahap berikutnya dilaksanakan, ternyata tujuan akhir yang ingin dicapai dari
Inpres tersebut yaitu menurunnya kejadian penyakit diare tidak kunjung terwujud.
Penyakit diare selalu dalam posisi lima besar penyakit di masyarakat dan menjadi
kontributor yang cukup besar terhadap terjadinya kematian penduduk.
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program sanitasi yang gagal dimasa lalu, maka
dilakukan kajian untuk menemukan penyebab utama kegagalan tersebut. Hasilnya
dijadikan sebagai prinsip dalam pendekatan pembangunan sanitasi berikutnya dan juga
digunakan sebagai pendekatan untuk mencegah stunting, prinsip-prinsip tersebut adalah
sebagai berikut:
A. Tanpa subsidi.
Pada program sanitasi terdahulu ciri khas yang menonjol adalah adanya subsidi bagi
masyarakat untuk membangun sarana sanitasinya baik berupa material sanitasi maupun
dibangunkan secara penuh. Namun kenyataannya subsidi tidak bisa memenuhi semua
kebutuhan masyarakat sehingga penerima bantuan hanya keluarga tertentu saja, dan
sering terjadi penerimanya dari golongan kerabat keluarga penentu keputusan, yang
belum tentu membutuhkan bantuan tersebut.
Oleh karena itu prinsip yang pertama adalah tidak boleh ada bantuan untuk masyarakat
dari pemerintah atau pihak lain untuk menyediakan sarana sanitasi dasarnya.
Penyediaan sarana sanitasi dasar adalah tanggung jawab masyarakat. Sekiranya
individu masyarakat belum mampu menyediakan sanitasi dasar yang improve sesuai
dengan standar teknis jamban keluarga yang ditetapkan oleh WHO, maka masyarakat
bisa memulai dengan membangun sarana sanitasi yang sederhana namun tetap
berfungsi untuk memutus alur penularan penyakit. Setelah masyarakat merasakan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 37
manfaatnya dan memiliki dana yang cukup maka akan mendorong untuk meningkatkan
kualitas jamban yang dimiliki.
Di dalam pendekatan STBM-Stunting, prinsip ini juga diterapkan. Tidak boleh ada subsidi
yang diberikan kepada masyarakat untuk mencegah stunting, baik dalam penyediaan
makanan bagi ibu hamil maupun makanan bagi bayi dan anak. Subsidi hanya diberikan
pada kondisi khusus, yaitu untuk pengobatan (kuratif) misalnya pemberian vitamin dan
makanan tambahan untuk ibu hamil atau anak bayi yang kekurangan nutrient tertentu
atau menderita sakit infeksi.
B. Masyarakat sebagai pemimpin
Program sanitasi terdahulu sifatnya topdown, masyarakat kurang diberi kesempatan
untuk berpartisipasi dan memutuskan pilihan teknologi, lokasi, model, dan pelaksanaan
pembangunannya. Masyarakat hanya dijadikan obyek sasaran program tanpa diberi
peran yang maksimal, hanya mengikuti apa yang sudah diinstruksikan dari atas dalam
dokumen program. Akibanya masyarakat tidak merasa memiliki dan tingkat partisipasinya
rendah terutama dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana yang dibangun.
Oleh karena itu prinsip yang kedua yaitu memposisikan masyarakat sebagai pemimpin
yang menentukan keputusan dan berinisiatif pembangunan sarana sanitasinya dan untuk
mencegah stunting. Jenis pilihan teknologi sanitasi, kualitas material, jenis makanan yang
akan dikonsumsi, pendanaannya, serta penggunaan dan pemeliharaannya ditentukan
sendiri oleh masyarakat. Pihak luar bertindak sebagai fasilitator yang berfungsi
memudahkan masyarakat mengakses material sanitasi dan gizi baik yang diperlukan dan
sumber pendanaan yang diperlukan. Dalam praktiknya, biasanya akan tercipta natural
leader di masyarakat yang akan menggerakkan masyarakat lainnya untuk melakukan
perubahan memperbaiki kondisi sanitasi dan pencegahan stunting.
C. Tidak menggurui/memaksa
Program sanitasi terdahulu telah dirancang oleh pemerintah atau pihak donor
berdasarkan kajian yang mereka lakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan
masyarakat. Seolah-olah pihak luar tersebut mengetahui dengan pasti apa yang
dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pihak
luar merasa lebih tahu dan lebih ahli dalam menentukan kebutuhan masyarakat, namun
melupakan masyarakat yang sudah bertahun-tahun tinggal di wilayah tersebut dengan
kebiasaan dan budaya mereka. Pihak luar secara tidak sadar telah memaksa masyarakat
untuk menerima sesuatu yang baru yaitu sarana sanitasi yang telah ditetapkan teknologi
maupun modelnya.
Namun kenyataannya teknologi dan model sarana sanitasi tersebut tidak selalu cocok
bagi masyarakat. Begitu juga dengan upaya pencegahan stunting. Terkadang ada
program pemerintah maupun pihak donor yang kurang sesuai dengan kondisi di suatu
tempat, misalnya memperkenalkan hanya nasi sebagai karbohidrat di daerah yang
mayoritas penduduknya mengkonsumsi singkong atau sagu, atau memperkenalkan
makanan tambahan produksi industri yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh
masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya pihak luar tidak lagi memaksa masyarakat dan
seakan lebih tahu (menggurui) apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pihak luar
berperan sebagai fasilitator dan mendorong masyarakat untuk melakukan kajian
terhadap kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat yang dapat merugikan dirinya
sendiri serta menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 38
D. Totalitas
Program sanitasi terdahulu tidak banyak melibatkan masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana sanitasi yang dibangun. Hanya sebagian anggota masyarakat yang terlibat dan
menjadi sasaran penerima program bantuan pembangunan sarana air minum dan
jamban keluarga. Akibatnya masyarakat merasa keputusan yang ditetapkan bukan
merupakan keputusan kolektif masyarakat, serta membuat masyarakat yang tidak
menerima bantuan merasa iri dan menunggu bantuan berikutnya. Akibatnya tujuan yang
diharapkan tidak tercapai, kondisi sanitasi tetap buruk, dan transmisi penyakit tetap
terjadi dan masyarakat tetap dalam risiko terkena penyakit.
Oleh karena itu seluruh anggota masyarakat baik laki-laki atau perempuan, yang kaya
atau miskin, yang tua atau muda (totalitas) terlibat dalam analisa permasalahan,
perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana sanitasi dan
perubahan perilaku higiene dan saniter untuk mencegah stunting. Keputusan
masyarakat dan pelaksanaan secara kolektif adalah kunci keberhasilan STBM-Stunting.
Totalitas dimaksudkan pula selain semua golongan yang ada di masyarakat, juga
meliputi delapan pilar STBM-stunting untuk mencegah stunting secara maksimal, tidak
cukup satu atau dua pilar saja.
POKOK BAHASAN 5: STRATEGI STBM-STUNTING
Pendekatan STBM-stunting merupakan interaksi yang saling terkait antara ketiga strategi
pokok yang dilaksanakan secara terpadu, sebagai berikut:
A. Peningkatan Kebutuhan dan Permintaan Sanitasi-Stunting
Strategi peningkatan kebutuhan sanitasi-stunting merupakan upaya sistematis untuk
mendapatkan perubahan perilaku yang higienis, saniter, dan mencegah stunting, berupa:
Pemicuan perubahan perilaku;
Promosi dan kampanye perubahan perilaku hygiene, sanitasi, dan gizi secara
langsung;
Penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
Mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
Memfasilitasi terbentuknya komite/tim kerja masyarakat;
Mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi
melalui mekanisme kompetisi dan patokan (benchmark) kinerja daerah.
B. Peningkatan Layanan Penyediaan Sanitasi dan Pencegahan Stunting
Peningkatan penyediaan sanitasi dan pencegahan stunting yang diprioritaskan untuk
meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi
yang layak serta akses dan layanan gizi untuk mencegah stunting dilakukan melalui
beberapa kegiatan, diantaranya:
Mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi dan perbaikian/peningkatan
mutu gizi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
Menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi dan gizi;
Mengembangkan kapasitas pelaku pasar sanitasi dan gizi termasuk wirausaha
sanitasi dan gizi lokal;
Mempromosikan pelaku usaha sanitasi dalam rangka memberikan akses pelaku
usaha sanitasi lokal ke potensi pasar (permintaan) sanitasi on-site potensial.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 39
C. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif.
Strategi ini mencakup advokasi kepada para pemimpin pemerintah, pemerintah daerah,
dan pemangku kepentingan dalam membangun komitmen bersama untuk
melembagakan kegiatan pendekatan STBM-stunting yang diharapkan akan
menghasilkan:
Komitmen pemerintah daerah menyediakan sumber daya untuk melaksanakan
pendekatan STBM-stunting dan menyediakan anggaran untuk penguatan
institusi;
Kebijakan dan peraturan daerah mengenai program sanitasi dan pencegahan
stunting seperti Surat Edaran Kepala Daerah, SK Bupati/Walikota, Perda,
RPJMD, Renstra, dan lain-lain;
Terbentuknya lembaga koordinasi yang mengarusutamakan sektor sanitasi dan
gizi untuk meningkatkan akses sanitasi dan mencegah stunting, menghasilkan
peningkatan anggaran sanitasi-gizi daerah, koordinasi sumber daya dari
pemerintah maupun non-pemerintah;
Adanya tenaga fasilitator, pelatih STBM-stunting, dan kegiatan peningkatan
kapasitas;
Adanya sistem pemantauan hasil kinerja dan proses pengelolaan pembelajaran.
Strategi peningkatan kebutuhan dan permintaan STBM-stunting dapat dilaksanakan
terlebih dulu untuk memberikan gambaran kepada masyarakat sasaran tentang resiko
hidup di lingkungan yang kumuh, seperti mudah tertular penyakit yang disebabkan oleh
makanan dan minuman yang tidak higienis, lingkungan yang kotor dan bau, pencemaran
sumber air terutama air tanah dan sungai, daya belajar anak menurun, dan kemiskinan.
Salah satu metode yang dikembangkan untuk peningkatan kebutuhan dan permintaan
sanitasi-stunting adalah CLTS yang mendorong perubahan perilaku masyarakat sasaran
secara kolektif dan mampu membangun sarana sanitasi secara mandiri dan
menyediakan sarana untuk mencegah stunting sesuai kemampuan.
Peningkatan layanan penyediaan sanitasi dan gizi untuk mencegah stunting perlu
dilakukan untuk mendekatkan pelayanan jasa pembangunan sarana sanitasi dan
memudahkan akses oleh masyarakat, menyediakan bebagai tipe sarana yang terjangkau
oleh masyarakat dan opsi keuangan khususnya skema pembayaran sehingga
masyarakat yang kurang mampu memiliki akses terhadap sarana sanitasi yang layak.
Pendekatan ini dapat dilakukan tidak hanya dengan melatih dan menciptakan para
wirausaha sanitasi, namun juga memperkuat layanan melalui penyediaan berbagai
variasi/opsi jenis sarana yang dibangun, sehingga dapat memenuhi harapan dan
kemampuan segmen pasar. Infomasi yang rinci, akurat, dan mudah dipahami oleh
masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung promosi sarana sanitasi yang sehat
yang dapat disediakan oleh wirausaha sanitasi dan hal ini dapat disebarluaskan melalui
jejaring pemasaran untuk menjaring konsumen. Pengembangan pasar untuk
meningkatkan sarana gizi untuk mencegah stunting juga dapat dilakukan seperti
pengembangan pasar sanitasi.
Kedua strategi tersebut dapat berinteraksi melalui mekanisme pasar bila mendapatkan
dukungan dari pemerintah yang dituangkan dalam bentuk regulasi, kebijakan,
penganggaran dan pendekatan yang dikembangkan. Bentuk upaya tersebut adalah
penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mendukung kedua strategi berinteraksi. Ada
beberapa indikator yang dapat menggambarkan lingkungan yang kondusif antara lain:
Kebijakan,
Kelembagaan,
Metodologi pelaksanaan program,
Kapasitas pelaksanaan,
Produk dan perangkat,
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 40
Keuangan,
Pelaksanaan dengan biaya yang efektif,
Monitoring dan evaluasi.
POKOK BAHASAN 6: DELAPAN PILAR STBM-STUNTING
A. Pengertian pilar – pilar dalam STBM-Stunting
STBM-Stunting terdiri dari lima Pilar STBM dan tiga pilar pencegahan stunting, yaitu:
1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan di Rumah Tangga (PAMM-RT)
4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT)
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)
6. Gizi Ibu Hamil
7. Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)
8. Pemantauan Pertumbuhan.
Berikut penjelasan mengenai delapan pilar tersebut.
1. Pilar 1-Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku
BABS yang berpotensi menyebarkan penyakit. Perilaku Pilar ke-1 STBM diwujudkan
melalui kegiatan sedikitnya:
a. Membudayakan perilaku BAB sehat yang dapat memutus alur kontaminasi
kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan.
b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar
dan persyaratan kesehatan.
Dalam melakukan perilaku BAB yang benar, dibutuhkan sarana jamban yang sehat.
Kriteria jamban yang sehat terlihat pada gambar berikut:
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 41
Gambar 9. Kriteria Jamban Sehat
Standar dan persyaratan kesehatan bangunan jamban terdiri dari:
a. Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap),
Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan
cuaca dan gangguan lainnya.
b. Bangunan tengah jamban
Lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan urine) dengan konstruksi leher
angsa. Pada konstruksi sederhana (semi permanen) untuk daerah rawan/sulit air,
lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus diberi tutup.
Lantai Jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran
untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).
c. Bangunan Bawah
Merupakan bangunan penampungan, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja yang
berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja melalui
vektor pembawa penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung,
jenisnya dapat berupa Tangki Septik yang kedap dan tidak bocor (gambar 5) dan
Cubluk. Cubluk hanya boleh digunakan di pedesaan dengan kepadatan
penduduk rendah dan sulit air.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 42
Gambar 10. Tangki septik cor langsung tanpa sambungan
2. Pilar 2-Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
Perilaku Pilar ke-2 STBM, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang
mengalir diwujudkan melalui kegiatan sedikitnya:
a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun
secara berkelanjutan
b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air
mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
Hasil penelitian Laston (1992), Pinfold (1994), Curtis (2003), Luby et al (2005), dan
Burton et al (2011) menemukan bahwa mencuci tangan dengan menggunakan sabun
lebih efektif daripada mencuci tangan dengan menggunakan air saja. Perilaku ini sangat
efektif mencegah dan menurunkan insiden diare sebesar 42-53%. Dengan perilaku ini,
satu juta kematian akibat diare dapat dicegah.
Waktu kritis yang mengharuskan praktik cuci tangan pakai sabun untuk mencegah diare
dan ISPA (Tifus/Hepatitis A dan E/Polio):
1. Sebelum makan
2. Sesudah BAB
3. Sebelum mempersiapkan makan
4. Sesudah membersihkan kotoran bayi
5. Sebelum menyuapi anak.
3. Pilar 3- Pengelolaan Air Minum dan Makanan di Rumah Tangga (PAMM-RT)
Pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga
kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk
menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di
rumah tangga yang meliputi 6 prinsip Higiene Sanitasi Pangan: (1) Pemilihan bahan
makanan, (2) Penyimpanan bahan makanan, (3) Pengolahan bahan makanan, (4)
Penyimpanan makanan, (5) Pengangkutan makanan, (6) Penyajian makanan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 43
Perilaku Pilar ke-3 STBM diwujudkan melalui kegiatan sedikitnya:
a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan
bersih secara berkelanjutan
b. Menyediakan dan memeliharan tempat pengolahan air minum dan makanan rumah
tangga yang sehat.
A. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga, dilakukan dengan cara:
1. Pengolahan air baku, dilakukan apabila air baku keruh dengan cara
pengolahan awal:
a. Pengendapan dengan gravitasi alami
b. Penyaringan dengan kain
c. Penjernihan dengan bahan kimia/tawas
2. Pengolahan air minum di rumah tangga, dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan kualitas air yang layak untuk dikonsumsi dengan
menghilangkan bakteri dan kuman penyebab penyakit melalui:
a. Filtrasi (penyaringan), contoh: biosand filter, keramik filter.
b. Klorinasi, contoh: klorin cair, klorin tablet.
c. Koagulasi dan flokulasi (penggumpalan) contoh: pemberian bubuk
koagulan pada air baku.
d. Desinfeksi, contoh: merebus air, Sodis (Solar Water Disinfection).
3. Wadah Penyimpanan Air Minum. Setelah pengolahan air, tahapan
selanjutnya menyimpan air minum dengan aman untuk keperluan sehari-
hari, dengan cara:
a. Wadah penyimpanan; tertutup, berleher sempit atau lebih baik
dilengkapi dengan kran. Wadah penyimpanan dicuci setelah tiga hari
atau saat air habis, gunakan air yang sudah diolah sebagai air bilasan
terakhir
b. Penyimpanan air yang sudah diolah; disimpan dalam tempat yang
bersih dan selalu tertutup.
B. Pengelolaan Makanan tingkat Rumah Tangga
Pengolahan pangan yang baik dan benar akan menghasilkan pangan yang
bersih, sehat, aman dan bermanfaat serta tahan lama. Untuk menjamin
higiene sanitasi pangan perlu melaksanakan 6 prinsip higiene sanitasi
pangan berikut ini: (1) Pemilihan bahan makanan, (2) Penyimpanan bahan
makanan, (3) Pengolahan bahan makanan, (4) Penyimpanan makanan, (5)
Pengangkutan makanan, (6) Penyajian makanan.
Prinsip 1: Pemilihan Bahan Pangan
Ciri-ciri bahan pangan yang baik
1. Pangan hewani (berasal dari hewan):
a. Daging ternak:
Sapi: warna merah segar, serat halus, lemak lunak, warna kuning.
Kambing: warna merah jambu, serat halus, lemak keras warna putih,
berbau khas (prengus).
Unggas: warna putih kekuningan, lembek, tulangnya jelas warna
kekuningan. Bila dipotong sudah mati (bangkai) warna agak gelap, luka
potong lurus pada bekas sembelihan, dagingnya kenyal.
Ayam Kampung: daging agak kering dan langsing, otot jelas warna
kekuningan.
Ayam ras/broiler: daging lunak, agak basah dan motok, lebih jelas pada
kepala/jengger.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 44
b. Hati Sapi, kambing, ayam, ungags
Hati bagi mahluk hidup merupakan organ utama termasuk dalam tubuh hewan.
Hati hewan perlu perhatian yang lebih dibanding dengan organ jeroan yang lain
karena hati memiliki senyawa beracun lebih banyak dibandingkan dengan
bagian jeroan yang lain, hal ini disebabkan karena hati merupakan tempat
dimana racun dinetralisir sehubungan dengan sistem pencernaan.
Untuk mengkonsumsi hati hal yang perlu dilakukan adalah:
Cucilah hati berkali-kali hingga benar-benar bersih.
Setelah dicuci bersih rebus lah hati hingga matang
Baru kemudian diolah menjadi bahan makanan.
Hal ini sangat penting untuk setidaknya mengurangi bahaya yang muncul
apabila salah dalam mengolah hati.
Ciri-ciri hati yang segar adalah warna merah kecoklatan, lembut dan sangat
mudah hancur, namun apabila hati tersebut direbus akan mengeras.
c. Ikan segar
Warna kulit terang, cerah, dan tidak lebam.
Ikan bersisik masih melekat sisiknya dengan kuat, dan tidak mudah
rontok.
Mata melotot, jernih, dan tidak suram.
Daging elastis, bila ditekan tidak berbekas.
Insang berwarna merah segar dan tidak bau.
Tidak terdapat lendir berlebihan pada permukaannya.
Tidak berbau busuk, asam, atau bau asing yang lain dari biasanya.
Ikan akan tenggelam dalam air.
c. Ikan asin/kering
Cukup kering dan tidak busuk.
Daging utuh dan bersih, bebas serangga.
Bebas bahan racun seperti pestisida.
Tidak dihinggapi/daya tarik bagi lalat/serangga lain.
d. Telur
Tampak bersih, tidak terdapat noda, atau kotoran pada kulit.
Tidak pecah, retak, dan bocor.
Mempunyai lapisan zat tepung pada permukaan kulit.
Kulit telur kering dan tidak basah akibat dicuci.
Dikocok tidak kopyor (koclak).
Bila diteropong (canding) terlihat terang dan bersih.
Telur yang terbaik adalah yang diambil langsung dari kandang tanpa
perlakuan tambahan seperti pembersihan atau dilap karena akan
mempercepat pembusukan.
2. Pangan nabati (berasal dari tumbuhan)
a. Buah-buahan
Keadaan fisiknya baik, isinya penuh, kulit utuh, tidak rusak, atau kotor.
Isi masih terbungkus kulit dengan baik.
Warna sesuai dengan bawaannya, tidak ada warna tambahan, warna
buatan (karbitan), dan warna lain selain warna buah.
Tidak berbau busuk, bau asam/basi, atau bau yang tidak segar lainnya.
Tidak ada cairan lain selain getah aslinya.
Terdapat lapisan pelindung alam.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 45
b. Sayuran
Daun, buah, atau umbi dalam keadaan segar, utuh, dan tidak layu.
Kulit buah atau umbi utuh dan tidak rusak/pecah.
Tidak ada bekas gigitan hewan, serangga, atau manusia.
Tidak ada bagian tubuh buah yang ternoda atau berubah warnanya.
Bebas dari tanah atau kotoran lainnya.
c. Biji-bijian
Kering, isi penuh (tidak keriput dan warna mengkilap).
Permukaannya baik, tidak ada noda karena rusak, jamur atau kotoran
selain warna aslinya.
Biji tidak berlubang-lubang.
Tidak tercium bau lain selain bau khas biji yang bersangkutan.
Tidak tumbuh kecambah, tunas kecuali dikehendaki untuk itu (touge).
Biji yang masih baik akan tenggelam bila dimasukkan ke dalam air.
Perhatikan : Biji yang telah berubah warnanya atau bernoda atau
berjamur dan terasa pahit, jangan dimakan karena sangat
berkemungkinan mengandung aflatoksin yang dapat mematikan.
d. Bumbu kering
Keadaannya kering dan tidak dimakan serangga.
Warna mengkilap dan berisi penuh.
Bebas dari kotoran dan debu.
Penggunaan bumbu kering perlu diperhatikan agar diolah pada saat
dekat dengan waktu pengolahan pangan sehingga bumbu yang telah
diolah langsung bisa dipergunakan.
3. Pangan fermentasi
Pangan fermentasi adalah pangan yang diolah dengan bantuan mikroba seperti ragi
(yeast) atau cendawan (fungi).
a. Pangan fermentasi nabati seperti tauco, kecap, tempe, oncom, tempoyak,
bir, tape, dan lain-lain.
b. Pangan fermentasi hewani, seperti terasi, petis, cingcalo, atau daging asap.
Ciri-ciri pangan fermentasi yang baik:
a. Pangan tercium aroma asli pangan fermentasi dan tidak ada perubahan
warna, aroma, dan rasa.
b. Bebas dari cemaran serangga (ulat) atau hewan lainnya.
c. Tidak terdapat noda-noda pertumbuhan benda asing seperti spot-spot
berwarna, atau jamur gundul pada tempe atau oncom.
Bahaya kontaminasi pada pangan fermentasi: relatif hampir tidak ada,
hanya perubahan tekstur atau rasa (catatan: fermentasi tidak terjadi kalau
ada bakteri lain yang tumbuh).
4. Pangan olahan pabrik
Pangan pabrik adalah pangan yang diolah oleh pabrik pangan dan biasanya dikemas
dalam kaleng, botol plastik atau doos.
Ada yang dikemas dengan vacuum dan ada yang dalam cara biasa. Ciri pangan
olahan pabrik yang baik:
a. Terdaftar.
b. Kemasannya masih baik, utuh, tidak rusak, bocor, atau kembung.
c. Minuman dalam botol tidak berubah warna atau keruh serta tidak terdapat
gumpalan.
d. Belum habis masa pakai (belum kadaluwarsa).
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 46
e. Segel penutup masih terpasang dengan baik.
f. Mempunyai merk dan label yang jelas nama pabrik pembuatnya.
Prinsip 2: Penyimpanan Bahan Pangan
Ada empat cara penyimpanan pangan yang sesuai dengan suhunya, yaitu :
a. Penyimpanan sejuk (cooling), yaitu suhu penyimpanan 10o - 15oC untuk jenis
minuman, buah, dan sayuran.
b. Penyimpanan dingin (chilling), yaitu suhu penyimpanan 4o - 10oC untuk
bahan pangan berprotein yang akan segera diolah kembali.
c. Penyimpanan dingin sekali (freezing), yaitu suhu penyimpanan 0o - 4oC
untuk bahan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu sampai 24
jam.
d. Penyimpanan beku (frozen), yaitu suhu penyimpanan < 0oC untuk bahan
pangan protein yang mudah rusak untuk jangka waktu > 24 jam.
Untuk menghindari pencemaran, pengambilan dengan dilakukan dengan cara
First In First Out (FIFO), yaitu yang disimpan lebih dahulu digunakan dahulu
(antri), agar tidak ada pangan yang busuk dan memperhatikan waktu
kadaluarsa pangan
Prinsip 3: Pengolahan Pangan
Pengolahan pangan yang baik adalah yang mengikuti kaidah dari prinsip-prinsip
higiene dan sanitasi. Dapur yang memenuhi standar dan persyaratan higiene dan
sanitasi untuk mencegah risiko pencemaran (kontaminasi silang dan kontaminasi
ulang) terhadap pangan.
Beberapa hal yang penting dalam persiapan di dapur adalah:
a. Ventilasi harus cukup baik agar asap dan udara panas dapat keluar dengan
sempurna.
b. Lantai, dinding dan ruangan bersih dan terpelihara agar menekan
kemungkinan pencemaran terhadap pangan.
c. Meja peracikan bersih dan permukaanya kuat/tahan goresan agar bekas
irisan tidak masuk ke dalam pangan.
d. Ruangan bebas lalat dan tikus. Lalat dan tikus adalah sumber pencemar
yang cukup potensial pada pangan.
Cara mencegah lalat:
1). Menjaga kebersihan dari sisa pangan yang disukai lalat.
2). Memasang kawat kassa.
3). Memasang perangkap lalat (insect killer).
4). Mengalirkan suhu dingin pada pintu masuk (air curtain).
5). Memasang penangkap lalat (fly trap).
6). Memasang perekat lalat (reppelent) berupa kertas berisi lem dan pestisida.
7). Memasang kipas angin (fan).
8). Memasang lilin.
9). Menabur umpan lalat di halaman (tidak di ruangan dapur).
10).Menyemprot pestisida secara berkala (dilakukan sewaktu tidak beroperasi).
Cara mencegah tikus:
1). Tidak ada dinding rangkap pada dinding, langit-langit atau perabotan.
2). Tidak ada konstruksi bangunan yang berlubang (lubang limbah ditutup
kassa/teralis rapat).
3). Tidak terdapat celah diantara kayu yang berukuran di bawah 5 cm.
4). Tidak ada sudut gelap tumpukan barang bekas.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 47
5). Memasang perangkap tikus pada jalur lintasan tikus, seperti lem tikus
atau jepitan.
Peralatan masak dan peralatan makan dan minum
Peralatan adalah semua perlengkapan yang diperlukan dalam proses pengolahan
pangan, seperti pisau, sendok, kuali wajan, dan lain-lain. Peralatan yang bersih dan
siap dipergunakan sudah berada pada tempat masing-masing sehingga
memudahkan waktu mencari/mengambilnya.
Wadah Penyimpanan Pangan
a. Kuali, waskom, dan panci harus dalam keadaan bersih.
b. Peralatan untuk menyimpan pangan pada prinsipnya harus terpisah:
Pangan matang dan pangan mentah.
Bahan pangan kering dan bahan pangan basah.
Setiap jenis pangan
c. Penyimpanan terpisah dimulai dari wadah masing-masing jenis tempat
penyimpanan atau alat untuk menyimpan pangan.
d. Bilamana belum memungkinkan perlu diperhatikan cara pemisahan pangan
yang benar dan teliti untuk setiap jenis pangan yang berada di dalam ruangan
tempat penyimpanan.
Peracikan Bahan
a. Cucilah bahan pangan sampai bersih dengan air yang mengalir.
b. Potonglah bahan dalam ukuran kecil-kecil agar mudah masak.
c. Buanglah bagian yang rusak, layu atau bernoda.
d. Masukkan potongan bahan ke tempat yang bersih dan terlindungi dari
serangga.
e. Bahan siap dimasak.
f. Segerakan memasak dan jangan biarkan terlalu lama di luar kulkas.
Prinsip 4: Penyimpanan Pangan Masak
Pangan masak merupakan campuran bahan yang lunak dan sangat disukai bakteri.
Bakteri akan tumbuh dan berkembang dalam pangan yang berada dalam suasana
yang cocok untuk hidupnya sehingga jumlahnya menjadi banyak.
Suhu pangan masak yang cocok untuk pertumbuhan bakteri yaitu suhu yang
berdekatan dengan suhu tubuh manusia (37oC). Pada suhu ini pertumbuhan bakteri
akan sangat cepat. Pada suhu lebih dingin atau lebih panas dari 37 oC, bakteri akan
semakin lambat tumbuhnya. Pada suhu di bawah 10oC bakteri sama sekali tidak
tumbuh dan pada suhu 60oC bakteri mulai mati. Oleh karena itu untuk mencegah
pertumbuhan bakteri maka usahakanlah pangan selalu berada pada suhu dimana
kuman tidak tumbuh yaitu pada suhu di bawah 10 oC atau di atas 60oC.Suhu 10oC –
60oC sangat berbahaya, maka disebut “DANGER ZONE”.
Prinsip 5: Pengangkutan Pangan
Pengangkutan pangan yang sehat akan sangat berperanan di dalam mencegah
terjadinya pencemaran pangan. Pencemaran pada pangan masak lebih tinggi
resikonya daripada pencemaran pada bahan pangan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 48
Pangan siap saji lebih rawan terhadap pencemaran sehingga perlu perlakuan yang
ekstra hati-hati. Oleh karena itu dalam prinsip pengangkutan pangan siap santap
perlu diperhatikan sebagai berikut:
a. Setiap pangan mempunyai wadah masing-masing.
b. Isi pangan tidak terlampau penuh untuk mencegah terjadinya kondensasi.
Uap pangan yang mencair (kondensat) merupakan media yang baik untuk
pertumbuhan bakteri sehingga pangan cepat menjadi basi.
c. Wadah yang dipergunakan harus utuh, kuat dan ukurannya memadai dengan
pangan yang ditempatkan dan terbuat dari bahan anti karat atau bocor.
d. Pengangkutan untuk waktu yang lama harus diatur suhunya agar tetap panas
60°C atau tetap dingin 4°C.
e. Wadah selama dalam perjalanan tidak boleh selalu dibuka dan tetap dalam
keadaan tertutup sampai di tempat penyajian.
f. Kendaraan pengangkut disediakan khusus dan tidak digunakan untuk
keperluan mengangkut bahan lain.
Prinsip 6: Penyajian Pangan
Penyajian pangan merupakan rangkaian akhir dari perjalanan pangan. Pangan yang
disajikan adalah pangan yang siap santap.
Prinsip Penyajian
a. Prinsip wadah artinya setiap jenis pangan di tempatkan dalam wadah terpisah
masing-masing dan diusahakan tertutup terutama wadah yang berada tidak satu
level dengan wadah pangan lainnya.
Tujuannya adalah:
1). Pangan tidak terkontaminasi silang.
2). Bila satu tercemar yang lain dapat diamankan.
3). Memperpanjang masa saji pangan sesuai dengan tingkat kerawanan pangan.
b. Prinsip kadar air artinya pangan yang mengandung kadar air tinggi (kuah, soto,
saus), baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah pangan
cepat rusak.
Tujuan: mencegah pangan supaya tidak mudah rusak (basi)
c. Prinsip edible part artinya setiap bahan yang disajikan dalam penyajian adalah
merupakan bahan pangan yang dapat dimakan. Hindari pemakaian bahan yang
membahayakan kesehatan seperti stekker besi, tusuk gigi, atau bunga plastik.
Bahan yang tidak untuk dimakan harus segera dibersihkan dari tempat penyajian
manakala acara makan dimulai.
Tujuan: mencegah kecelakaan atau gangguan akibat salah makan
d. Prinsip pemisah artinya pangan yang ditempatkan dalam wadah yang sama
seperti pangan dalam doos atau rantang harus dipisah dari setiap jenis pangan
agar tidak saling mencampur aduk.
Tujuan: untuk mencegah kontaminasi silang
e. Prinsip panas yaitu setiap penyajian pangan yang disajikan panas diusahakan
tetap dalam keadaan panas seperti sop, gulai, soto, dan sebagainya. Untuk
mengatur suhu perlu diperhatikan suhu pangan sebelum ditempatkan dalam alat
saji panas (food warmer) harus masih berada di atas 60oC. Alat terbaik untuk
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 49
mempertahankan suhu penyajian adalah dengan bean merry (bak penyaji
panas).
Tujuan: untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan meningkatkan selera.
f. Prinsip bersih artinya setiap peralatan yang digunakan seperti wadah dan
tutupnya, doos atau piring/gelas/mangkok harus bersih dan baik. Bersih artinya
telah dicuci dengan cara higienis, baik artinya utuh, tidak rusak atau cacat atau
bekas pakai.
Tujuan: Untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang
estetis.
g. Prinsip handling artinya setiap penanganan pangan maupun alat makan tidak
kontak langsung dengan anggota tubuh terutama tangan dan bibir.
Tujuan:
1). Mencegah pencemaran dari tubuh.
2). Memberikan penampilan sopan dan baik.
Dengan penerapan prinsip higiene dan sanitasi, diharapkan keamanan pangan
meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat, sehingga produktifitas
meningkat.
4. Pilar 4-Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT)
Merupakan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan
prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang. Perilaku pilar ke-4 STBM
diwujudkan melalui kegiatan sedikitnya:
a. Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya
dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin.
b. Melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan
kembali (recycle)
c. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar
rumah.
5. Pilar 5-Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)
Melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa
kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu
kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai
penularan penyakit. Perilaku pilar ke-5 STBM diwujudkan melalui kegiatan sedikitnya:
a. Melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan
dan saluran pembuangan air limbah. Namun, jika pada kawasan permukiman
sudah tersedia sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dengan sistem
perpipaan atau tangki septik yang sesuai standar dilengkapi dengan bidang
resapan, air limbah jamban, dan non jamban dapat diolah secara tercampur.
b. Menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga
c. Memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.
6. Pilar 6- Gizi Ibu Hamil
Pencegahan stunting perlu dilakukan selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Oleh
karena itu, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Ibu Hamil untuk
menjaga kondisi gizinya, yaitu:
a. Calon pengantin dan ibu pra-hamil harus berada pada status gizi baik dan
tidak menderita kurang darah. Untuk mempersiapkan hal ini, calon pengantin
harus mengatur pola konsumsi makanan yang beraneka ragam dan bergizi
seimbang.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 50
b. Menunda kehamilan pada remaja sampai mereka berusia 20 tahun, sehingga
tubuhnya sudah siap menghadapi kehamilan.
c. Semua ibu hamil harus mengkonsumsi 1 tablet tambah darah setiap hari
selama kehamilannya, minimal 90 tablet berturut-turut.
d. Ibu hamil minum 1 tablet suplemen Multipel Mikronutrien (MMN) setiap hari
selama kehamilannya.
e. Ibu hamil yang menderita KEK harus mendapat makanan tambahan
pemulihan.
7. Pialr 7- Pemberian Makan Bayi dan Anak
Stunting disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya asupan gizi pada bayi
dan anak yang tidak baik yan disebabkan karena pemberian makan bayi dan anak yang
tidak baik. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut perlu dilakukan:
a. Pastikan pemberian ASI ekslusif pada bayi stunting
b. Pemberian MP ASI yang tepat dan baik mulai anak berumur 6 bulan, dengan
penambahan tabur gizi pada makanan.
c. Pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun
8. Pilar 8- Pemantauan Pertumbuhan
Untuk mencegah stunting, perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan bayi dan anak
secara rutin, diantaranya dengan cara:
a. Pemberian 1 kapsul vitamin A warna merah (200.000 SI) saat pertama kali
dideteksi.
b. Selanjutnya mendapat 1 kapsul vitamin A warna merah (200.000 SI) 2 kali
dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus.
c. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan di posyandu.
d. Cek KMS untuk imunisasi dasar lengkap.
B. Penyelenggaraan pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting
Penyelenggara pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting adalah masyarakat, baik yang terdiri
dari individu, rumah tangga maupun kelompok-kelompok masyarakat. Pihak luar
termasuk pemerintah dan lembaga swadya masyarakat, hanya sebagai fasilitator yang
bertindak sebagai pendorong dan memicu masyarakat untuk melakukan kajian terhadap
masalah sanitasi dan gizi yang ada di lingkungan mereka. Selanjutnya setelah
masyarakat menyampaikan perasaan tidak senang/suka dengan kondisi sanitasi dan
gizi/stunting yang buruk dan ingin berubah, kemudian difasilitasi agar dapat mengakses
teknologi dan material sanitasi dan gizi maupun pendanaan untuk membangun sarana
sanitasi dan perbaikan gizi sesuai dengan kemampuan sendiri.
C. Manfaat pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting
Terselenggaranya delapan pilar STBM-Stunting akan membantu masyarakat untuk
mencapai tingkat higinitas yang paripurna, terwujudnya lingkungan yang bersih dan
sehat, dan kondisi gizi yang lebih baik yang akan meningkatkan martabat masyarakat
karena terhindar dari predikat desa/kelurahan yang “jorok”, menghindarkan mereka dari
risiko kesakitan dan kematian akibat sanitasi yang tidak sehat, dan mencegah terjadinya
stunting.
D. Tujuan Pelaksanaan 8 Pilar STBM-Stunting
Pelaksanaan 8 pilar STBM-Stunting bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat
yang higienis, saniter, menerapkan pola hidup dengan gizi baik secara mandiri yang
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 51
meliputi lima pilar STBM dan 3 pilar pencegaha stunting dalam rangka meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya secara mandiri dan berkeadilan.
POKOK BAHASAN 7: TANGGA PERUBAHAN PERILAKU VISI STBM-
STUNTING
Menurut Grimley dan Prochaska (1997) perubahan kebiasaan atau perilaku tidak terjadi
secara otomatis, akan tetapi terjadi secara bertahap, umumnya mengikuti tangga
perubahan perilaku “The stages of behavioral change“ sebagaimana proses yang
ditunjukkan gambar berikut:
Gambar 11 Tangga Perubahan Perilaku
Perilaku baru yang diperkenalkan petugas kesehatan kepada masyarakat, pada tahap
awal, masyarakat akan menilai (perenungan/pre-contemplation) perilaku baru tersebut,
apakah akan menimbulkan masalah atau malah sebaliknya justru baik dan sehat.
Jika penilaian/perenungan mereka baik, maka akan berlanjut dengan tahapan kedua
“sadar akan/paham/contemplation“. Kesadaran masyarakat akan perilaku baru yang
diperkenalkan diikuti dengan tahapan perubahan ke-3 yakni menaruh minat untuk
mencoba bertindak melakukan perilaku baru “preparation “.
Jika masyarakat merasakan manfaat dalam proses mencoba perilaku baru, maka
berlanjut dengan tindakan melakukan perilaku baru “action“. Demikian perilaku baru
dilakukan menjadi kebiasaan sehari-hari dan dilakukan secara berkesinambungan
“maintenance“.
A. Tangga Perubahan Perilaku Sanitasi
Tangga perubahan perilaku higiene dan sanitasi masyarakat adalah tahap
perkembangan perubahan perilaku dari kebiasaan awal yang masih buang air besar
sembarangan, tidak berperilaku cuci tangan dengan benar, tidak mengelola sampah dan
limbah cair rumah tangga berubah mempraktikkan perilaku higienis dan saniter dengan
budaya sehari-hari hidup bersih dan sehat.
Bila budaya masyarakat sudah mempraktikkan perilaku higinies dan saniter secara
permanen maka sarana sanitasi menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan sehingga
akan terjadi kondisi sanitasi total sesuai dengan tujuan dari pendekatan STBM ini.
Tangga perubahan perilaku (terlihat dalam gambar di bawah), belajar dari pengalaman
global, diketahui perilaku higiene tidak dapat dipromosikan untuk seluruh rumah tangga
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 52
secara bersamaan. Promosi perubahan perilaku kolektif harus berfokus pada satu atau
dua perilaku yang berkaitan pada saat bersamaan.
Gambar 12 Tangga Perubahan perilaku STBM
1. Perilaku BABS
Perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) adalah kebiasaan/praktik budaya
sehari-hari masyarakat yang masih membuang kotoran/tinjanya di tempat yang terbuka
dan tanpa ada pengelolaan tinjanya. Tempat terbuka untuk melakukan BABS ini
biasanya dilakukan di kebun, semak-semak, hutan, sawah, sungai, maupun di lokasi-
lokasi terbuka yang memang dijadikan sebagai lokasi BABS secara kolektif oleh
masyarakat seperti jamban helikopter/jamban plung lap (jamban yang dibuat tanpa ada
lubang septik langsung dibuang ke tempat terbuka seperti sungai, rawa, dll). Kebiasaan
BABS ini karena tidak adanya pengelolaan tinja yang memenuhi syarat-syarat
kesehatan menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan baik untuk individu
yang melakukan praktik BABS maupun komunitas lingkungan tempat hidupnya.
Kondisi masyarakat seperti ini perlu dilakukan sebuah kegiatan untuk melakukan
perubahan perilaku secara kolektif dengan pendekatan STBM.
Hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan kondisi masyarakat seperti ini adalah:
- Diadakan pemicuan ke masyarakat yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan atau
masyarakat yang sudah terlatih menjadi fasilitator STBM.
- Dari pemicuan tersebut diharapkan munculnya natural leader atau komite yang
dibentuk oleh komunitas masyarakat tersebut.
- Komite yang terbentuk mempunyai rencana aksi yang sistematis dalam rangka
menuju status SBS.
- Adanya kegiatan pemantauan secara terus menerus yang dilakukan oleh individu
maupun kelompok dari masyarakat tersebut.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 53
- Tersedianya peningkatan penyediaan akses sanitasi atau layanan pemenuhan akses
sanitasi untuk masyarakat dengan kualitas sesuai dengan standar kesehatan dengan
harga yang terjangkau.
2. Perilaku SBS
Perilaku SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) adalah adalah kebiasaan/praktik
budaya sehari-hari masyarakat yang tidak lagi membuang kotoran/tinjanya di tempat
yang terbuka dan sudah dilakukan pengelolaan tinjanya yang efektif untuk memutus
rantai penularan penyakit. Perilaku SBS ini biasanya diikuti dengan kemauan
masyarakatnya yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan akses sarana
sanitasi yang dimulai dari sarana jamban sehat paling sederhana sampai dengan tingkat
sarana jamban yang sudah bagus sistem pengelolaannya seperti IPAL komunal maupun
IPAL terpusat. Kemauan serta komitmen dari masyarakat ini dilakukan secara kolektif
dan partisipatif dalam mengambil keputusannya.
Ketika masyakat secara keseluruhan sudah berperilaku SBS maka dikatakan komunitas
tersebut mencapai kondisi Desa/Kelurahan SBS/ODF dimana kondisi komunitas
tersebut dengan kondisi sebagai berikut:
- 100% masyarakat sudah berubah perilakunya dengan status SBS (sudah terverifikasi
oleh tim verifikasi dari puskesmas setempat),
- Adanya rencana untuk merubah perilaku higienis lainnya,
- Adanya aturan dari masyarakat untuk menjaga status SBS,
- Adanya pemantauan dan verifikasi secara berkala.
3. Perilaku Higienis dan Saniter
Perilaku Higienis dan Saniter dalam dokumen ini diartikan sebagai kebiasaan/praktik
budaya sehari-hari masyarakat yang sudah tidak lagi BAB sembarangan dengan akses
sarana sanitasi jamban yang sehat dan berperilaku higienis saniter lainnya yang
merupakan bagian dari salah satu 4 pilar yang lainnya seperti berperilaku cuci tangan
pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah, dan
mengelola limbah cair rumah tangga.
Ketika masyarakat secara keseluruhan sudah berperilaku higienis dan saniter maka
dikatakan komunitas tersebut mencapai kondisi Desa/Kelurahan STBM dimana kondisi
komunitas tersebut dengan kondisi sebagai berikut:
- 100% masyarakat sudah berubah perilakunya dengan status Desa/Kelurahan SBS,
(sudah terverifikasi oleh tim verifikasi dari puskesmas setempat),
- Terjadi peningkatan kualitas sarana sanitasi yang ada,
- Terjadi perubahan perilaku higienis saniter lainnya di masyarakat,
- Adanya upaya pemasaran dan promosi sanitasi untuk pilar-pilar STBM yang lainnya,
- Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala.
4. Perilaku Sanitasi Total
Perilaku Sanitasi Total adalah kebiasaan/praktik budaya sehari-hari masyarakat yang
sudah mempraktikkan perilaku higienis sanitasi secara permanen dimana kebiasaan ini
meliputi (i) tidak buang air besar sembarangan; (ii) mencuci tangan pakai sabun; (iii)
mengelola air minum dan makanan yang aman; (iv) mengelola sampah dengan aman;
dan (v) mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
Ketika masyakat secara keseluruhan sudah berperilaku sanitasi total maka dikatakan
komunitas tersebut mencapai kondisi Desa/Kelurahan STBM dengan Kondisi Sanitasi
Total.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 54
B. Tangga perubahan perilaku asupan gizi
Mengacu pada tangga perubahan perilaku “The stages of behavioral change“
sebagaimana disebutkan diatas, bahwa masyarakat mau dan bersedia serta terbiasa
mengkonsumsi makanan dengan gizi baik, dimulai dengan perenungan informasi baru
sampai tindakan memelihara asupan gizi baik sebagai berikut :
1) Pre contemplation/perenungan
Masyarakat akan menilai (perenungan) perilaku baru yang yang diperkenalkan
oleh petugas kesehatan kepada masyarakat. Asupan gizi baik akan dinilai
(perenungan), apakah akan menimbulkan masalah atau malah sebaliknya justru
berdampak baik sehingga bayi dan anak tumbuh normal dan ibu menjadi lebih
sehat. Jika penilaian/perenungan mereka baik dengan melihat, memperhatikan
dan mengamati bayi dan anak serta ibu yang menerapkan asupan gizi baik dan
ternyata positif, maka masyarakat tersebut akan berlanjut ke tangga berikutnya.
2) Contemplation/sadar akan manfaat
Setelah melakukan penilaian dan perenungan, masyarakat mulai sadar dan
paham akan perilaku asupan gizi baik yang diperkenalkan petugas kesehatan
melalui teknik pemicuan. Tangga perubahan ini ditandai dengan pikiran yang
positif, seperti: anggukan kepala, penyataan, ataupun komitmen untuk berubah
pada saat pemicuan yang dilakukan petugas.
3) Preparation/menaruh minat dan mencoba
Masyarakat mulai mencoba mempraktikkkan perilaku terkait asupan gizi baik
seperti:
a) Pada saat ibu hamil:
oSetiap ibu hamil mencari, menemukan, dan meminum tablet tambah darah,
minimal 90 tablet selama kehamilan.
o Kesehatan ibu harus tetap dijaga agar tidak sakit.
b) Pada saat bayi lahir:
o Melakukan persalinan ke bidan atau dokter terlatih.
o Begitu bayinya lahir, ibu bersalin melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
oIbu mencari, menemukan, dan minum 2 kapsul vitamin A merah di masa
nifas.
o Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi ASI Ekslusif.
oMelakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi setiap bulan
di posyandu.
c) Pada saat bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun
o Mulai usia 6 bulan, tetap melanjutkan pemberian ASI, mencari, menemukan
dan memberi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) kepada bayinya sampai
berusia 2 tahun.
o Mencari, menemukan, dan memberi bayi dan anak kapsul vitamin A, taburia,
dan imunisasi dasar lengkap dari/di puskesmas.
o Aktif dengan inisiasi sendiri memantauan pertumbuhan dan perkembangan
setiap bulan di posyandu.
o Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupannya
dan membimbing keluarganya sehari.
4) Action/melakukan
Masyarakat mulai menjadikan asupan gizi baik menjadi kebiasaan sehari-hari
sebagaimana praktik asupan gizi di tangga ketiga. Jika kebiasaan tersebut tidak
terpenuhi maka masyarakat berusaha untuk menemukan dan mengusahakan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 55
sendiri baik dengan berkebun sayur, menciptakan apotik hidup, maupun membeli
kebutuhan asupan gizi baik di pasar.
5) Maintenance/menjadikan kebiasaan dan kebutuhan
Masyarakat memelihara dan melestarikan kebiasaan asupan gizi baik untuk
kebutuhannya dan keluarganya.
C. Tangga perubahan perilaku visi STBM-Stunting
Untuk mencegah dan menurunkan kejadian stunting serta untuk meningkatkan perilaku
sanitasi total, perubahan perilaku STBM dan stunting perlu dilaksanakan secara
terintegrasi. Integrasi kegiatan STBM dan stunting perlu dilakukan secara bertahap.
Berikut adalah tangga perubahan perilaku visi STBM-Stunting:
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 56
Gambar 13 Tangga Perubahan Perilaku STBM-Stunting
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 57
VIII. REFERENSI
Andrew J Prendergast, Jean H Humphrey. The Stunting Syndrome in Developing
Countries.Paediatrics and International Child Health. Vol.34 no 4, 2014 p 250-
265.
Black, R.E., et.al., 2012. Maternal and Child Undernutrition and Overweight in
Low Income and Middle-Income Countries. Lancet 202, no. 9890 (2012): 427-
451.
Chase, C and Ngure, F, 2016. Multisectoral Approaches to Improving Nutrition:
Water, Sanitation and Hygiene. Water and Sanitation Program Technical Paper,
the World Bank.
Environmental Health Perspective Volume 112 no 11, November 2014, Beyond
Malnutrition The role of Sanitatiin in Stunted Grow.
Institute for Development Studies, Working Paper184, Subsidy or Self-Respect
Total Community Sanitation in Bangladesh, Kamal Kar, September 2003.
Kemenkes RI, 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang
STBM
Kemenkes RI, Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan, Kurikulum dan Modul Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan: Buku Sisipan STBM, Jakarta, 2013.
Kemenkes RI, 2012. Materi Advokasi STBM.
Kemenkes RI, Dit. Penyehatan Lingkungan, Modul Hiegiene Sanitasi Makanan
dan Minuman, 2012.
Nutrition Landscape Informtion System (NLIS) WHO, 2010
Peter Katona and Judit Katona. The Interaction between Nutrition and Infection.
Clinical Practice. CID 2008: 46. p 1582-1588.http://ad.Oxfordjournals.org.
September, 2015
Sejarah Sanitasi, Seri AMPL 23,www.ampl.or.id
Update STBM, www.stbm-indonesia.org
100 Kabupaten/Kota Prioritas Intervensi Anak Kerdil (Stunting), Volume 2,
Setneg, TNP2K, 2017.
IX. LAMPIRAN (Terlampir)
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 58
MODUL MI.2
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM STBM-STUNTING
I. DESKRIPSI SINGKAT
Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam
pembangunan kesehatan. Secara spesifik, Permenkes No.65/2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan menyebutkan ada 6 faktor utama pentingnya pemberdayaan masyarakat.
1) Dari hasil kajian, ternyata 70% sumber daya pembangunan nasional berasal dari
kontribusi/partisipasi masyarakat. 2) Pemberdayaan masyarakat yang berazazkan
gotong royong merupakan budaya bangsa yang perlu dilestarikan. 3) Perilaku
masyarakat merupakan faktor penyebab utama terjadinya masalah kesehatan, oleh
sebab itu masyarakat sendirilah yang dapat menyelesaikan masalahnya dengan
pendampingan/bimbingan pemerintah. 4) Pemerintah mempunyai keterbatasan
sumber daya dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang semakin
kompleks. 5) Potensi masyarakat meliputi kepemimpinan, pengorganisasian,
pembiayaan, bahan dan alat, pengetahuan, teknologi, dan kemampuan membuat
keputusan perlu dioptimalkan. 6) Upaya pencegahan lebih efektif dan efisien
dibanding pengobatan. Masyarakat mempunyai kemampuan untuk melakukan upaya
pencegahan apabila dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat, terutama untuk
berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan salah satu cara untuk
merubah perilaku masyarakat untuk tercapainya 5 pilar STBM. Sedangkan STBM-
Stunting merubah perilaku agar masyarakat mengikuti 8 pilar. Untuk itu keberhasilan
STBM-Stunting memerlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat melalui
upaya pemberdayaan masyarakat.
Dalam modul ini akan dibahas tentang pengertian partisipasi masyarakat, tingkatan
partisipasi masyarakat, pengertian pemberdayaan masyarakat, prinsip dasar
pemberdayaan masyarakat, tahapan pemberdayaan masyarakat, dan penerapan
pemberdayaan masyarakat dalam STBM-Stunting.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan pemberdayaan
masyarakat dalam STBM-Stunting.
B. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:
1. Menjelaskan partisipasi masyarakat.
2. Menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam STBM-Stunting.
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai
berikut:
A. Pokok Bahasan 1: Partisipasi Masyarakat
a. Pengertian partisipasi masyarakat
b. Tingkatan partisipasi masyarakat
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 59
B. Pokok Bahasan 2: Pemberdayaan Masyarakat dalam STBM-Stunting
a. Pengertian pemberdayaan masyarakat
b. Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat.
c. Tahapan pemberdayaan masyarakat.
d. Penerapan pemberdayaan masyarakat dalam STBM-Stunting.
IV. METODE
Ceramah tanya jawab, curah pendapat, dan bermain peran.
V. MEDIA DAN ALAT BANTU
Bahan tayang, LCD proyektor, komputer, flipchart, spidol, meta plan, kain tempel,
modul, dan panduan bermain peran.
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 3 jam pelajaran (T=1
jpl, P=2 jpl, dan PL=0 JPL) @45 menit. Untuk mempermudah proses pembelajaran
dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta, dilakukan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut:
Langkah 1. Pengkondisian (5 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Fasilitator memulai kegiatan dengan menyapa peserta dengan ramah dan
hangat.
b. Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan
perkenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi
tempat bekerja, dan materi yang akan disampaikan.
c. Sampaikan tujuan pembelajaran materi ini dan pokok bahasan yang akan
disampaikan dengan menggunakan bahan tayang.
d. Minta seluruh peserta untuk memperkenalkan diri dengan cepat.
2. Kegiatan Peserta
Peserta memperkenalkan diri dengan menyebut nama, pekerjaan, dan asal
instansinya.
Langkah 2. Pembahasan per materi (120 menit)
1. Pokok Bahasan 1: Partisipasi Masyarakat (35 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Menyampaikan bahwa PB-1 adalah Partisipasi Masyarakat yang akan
disampaikan selama 35 menit. Materi pada PB-1 terdiri dari dua SPB yaitu
Pengertian Partisipasi Masyarakat dan Tingkatan Partisipasi Masyarakat.
b. Menyampaikan Pengertian Partisipasi Masyarakat melalui metode ceramah
tanya jawab selama 10 menit.
c. Memandu materi Tingkatan Partisipasi Masyarakat selama 20 menit
menggunakan metode curah pendapat.
1. Minta setiap peserta membuat gambar dalam selembar kertas A4 tentang
sebuah “situasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan”
berdasarkan pengalamannya masing-masing (pernah mengikuti, pernah
melihat atau pernah mendengar).
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 60
2. Sementara peserta membuat gambar, fasilitator menyiapkan kartu-kartu
yang bertuliskan tingkatan partisipasi yang terdiri dari 4 kriteria (tingkat
terendah sampai dengan tertinggi):
Menerima Informasi
Membuat keputusan
Diajak Berunding secara bersama-sama
antara masyarakat dan
pihak luar
Mendapatkan wewenang
untuk mengatur sumber
daya dan membuat
keputusan
3. Tempelkan keempat tingkatan tersebut pada dinding atau kain tempel
tanpa memberikan urutan tingkatan partisipasi.
4. Setelah peserta selesai menggambar, minta untuk menempelkan/atau
menempatkan gambar-gambar mereka di kain tempel/dinding atau di
lantai yang sesuai atau mendekati dengan judul masing-masing gambar
partisipasi.
5. Minta peserta menjelaskan maksud dari gambar-gambar tersebut (secara
acak) untuk setiap kelompok.
6. Minta peserta untuk membuat peringkat tingkatan partisipasi dari yang
terendah sampai tertinggi (dimulai dengan tingkat terendah dan tertinggi,
baru kemudian yang ada diantaranya).
7. Tanyakan pada tingkat partisipasi mana yang dibutuhkan dan harusnya
terjadi dalam proses pelaksanaan STBM-Stunting, dan apa alasan-alasan
mendasarnya? Ajak peserta berdiskusi sekitar 5-10 menit untuk
mendeskripsikan ke 4 tingkatan tersebut, kemudian minta peserta untuk
memilih (voting) tentang tingkatan yang seharusnya terjadi dalam STBM-
Stunting.
8. Jelaskan bahwa pada umumnya dalam pembangunan, terdapat berbagai
tingkat partisipasi di masyarakat dan tidak ada tingkatan yang salah.
Tingkat yang lebih tinggi tidak berarti hanya dapat dicapai dengan
melewati tingkat yang lebih rendah secara berjenjang. Namun, dari
semua tingkat yang ada, yang diharapkan oleh STBM-Stunting adalah
tingkatan dimana masyarakat harus mendapatkan wewenang untuk
mengatur sumber daya dan membuat keputusan. Alasan
mendasarnya adalah bahwa proses STBM-Stunting adalah proses
pemberdayaan yang menempatkan masyarakat untuk memutuskan
sendiri dan menggunakan sumberdaya mereka secara mandiri untuk
merencanakan dan melakukan tindakan perubahan perilaku. Hal tersebut
harus mereka dapatkan sebagai kewenangan mereka sendiri.
9. Akhiri dengan kesepatan dari hasil pilihan tersebut dan alasan
mendasarnya.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 61
2. Kegiatan Peserta
a. Menyampaikan pertanyaan atau masukan serta menjawab pertanyaan
Fasilitator.
b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan curah pendapat dengan mengikuti
kegiatan sesuai panduan fasilitator.
B. Pokok Bahasan 2: Pemberdayaan Masyarakat
1. Kegiatan Fasilitator
a. Menyampaikan bahwa PB-2 adalah tentang Pemberdayaan Masyarakat yang
akan disampaikan selama 85 menit. Materi pada PB-2 terdiri dari Pengertian
Pemberdayaan Masyarakat, Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat,
Tahapan Pemberdayaan Masyarakat, dan Penerapan Pemberdayaan
Masyarakat dalam STBM-Stunting.
b. Melakukan curah pendapat, dengan meminta peserta bercerita singkat
tentang situasi masyarakat yang disebut “berdaya”. Catat poin-poin penting
sebagai dasar dalam merumuskan pengertian, prinsip dasar hingga tahapan
pemberdayaan masyarakat. Lakukan curah pendapat untuk melengkapinya.
c. Menyampaikan Pengertian dan Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat
melalui ceramah Tanya jawab selama 10 menit, berdasarkan hasil curah
pendapat.
d. Menyampaikan tahapan pemberdayaan masyarakat dan dikaitkan dengan
tangga perubahan perilaku (tidak tahu, tahu/sadar, mau, mampu melakukan)
yang dipelajari pada MI.1 dengan melakukan curah pendapat selama 10
menit.
e. Memandu dengan metode bermain peran untuk membahas dan menganalisis
materi Sub Pokok Bahasan “Penerapan Pemberdayaan Masyarakat dalam
STBM-Stunting”. Bermain peran dilakukan selama 60 menit.
f. Menggunakan kelompok yang sama dengan kelompok sebelumnya.
Menjelaskan bahwa Kelompok-1 menggunakan skenario-1, kelompok-2
menggunakan skenario 2 dan kelompok-3 menggunakan skenario 3. Bagikan
Lembar Panduan Bermain Peran LP 2.1 kepada setiap kelompok sesuai
skenarionya masing-masing.
g. Berikan waktu 15 menit untuk setiap kelompok melakukan persiapan dan 15
menit untuk setiap kelompok memperagakan skenario yang mereka dapatkan
sesuai kelompok.
h. Setelah semua kelompok selesai memperagakan perannya, tanyakan:
i. Apa yang dirasakan peserta sebagai Tim Fasilitator Pemicuan STBM-
Stunting?
ii. Pembelajaran apa yang diperoleh dari permainan tersebut, dikaitkan
antara peran masyarakat dengan beberapa stakeholdernya, peran orang
luar sebagai fasilitator?
iii. Apakah peragaan tersebut membantu pemahaman mereka tentang
penerapan pemberdayaan masyarakat dalam STBM-Stunting?
i. Jelaskan rangkuman materi tentang penerapan pemberdayaan masyarakat
dalam STBM-Stunting bahwa “proses pemberdayaan masyarakat dalam
STBM-Stunting harus mampu menempatkan dan memberi kewenangan
penuh kepada masyarakat untuk mengenali dan menganalisis
masalahnya, mengidentifikasi pilihan-pilihan solusinya, merencanakan
tindakannya hingga membentuk panitia atau komite untuk memantau
rencana tindakan mereka secara mandiri”.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 62
2. Kegiatan Peserta
a. Menyampaikan pertanyaan, masukan, dan menjawab pertanyaan Fasilitator.
b. Berpartisipasi aktif dalam curah pendapat Berpartisipasi aktif dalam kegiatan
bermain peran dengan mengikuti kegiatan sesuai Lembar Panduan
Bermain Peran-LP II.1.
c. Menyampaikan pendapat dan pandangan dalam pembelajaran hasil diskusi
kelompok dan bermain peran.
Langkah 3. Rangkuman (5 Menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Merangkum sesi pembelajaran.
b. Mempersilahkan peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas.
c. Memfasilitasi pemberian jawaban, baik dari fasilitator maupun peserta lain.
d. Meminta komentar, penilaian, saran, dan kritik dari peserta pada kertas
evaluasi yang telah disediakann tentang proses dan hasil pembelajaran
Modul ini.
e. Menutup sesi pembelajaran dengan memastikan TPU dan TPK telah
tercapai.
2. Kegiatan Peserta
a. Berpartisipasi aktif untuk memberikan pertanyaan, masukan, penilaian, saran,
dan kritik.
b. Membalas salam.
VII. URAIAN MATERI
POKOK BAHASAN 1: PARTISIPASI MASYARAKAT
A. Pengertian Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan
dan melaksanakan keputusan (WHO, 2002). Ditinjau dari konteks kesehatan, partisipasi
adalah keikutsertaan dan kemitraan masyarakat dan fasilitator (pemerintah, LSM, mitra
pembangunan) dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan,
pemanantauan dan penilaian kegiatan dan program kesehatan, serta memperoleh
manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka membangun kemandirian masyarakat
(Permenkes No. 65/2013).
Dalam pendekatan STBM dan pendekatan partisipatif lainnya, partisipasi atau
keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak diperlukan.
Kunci partisipasi masyarakat dalam STBM-stunting adalah:
Menempatkan STBM-stunting sebagai inisiatif masyarakat,
Total atau keseluruhan sebagai kunci utama, artinya keputusan ada di tangan
masyarakat dan pelaksanaan dilakukan bersama (kolektif),
Solidaritas masyarakat (laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda) sangat
penting dan mereka terlibat secara aktif dalam STBM-stunting,
Semua dibuat oleh masyarakat, tidak ada campur tangan pihak luar, dan
biasanya akan muncul “natural leader” di masyarakat.
B. Tingkatan Partisipasi Masyarakat
Kata partisipasi masyarakat sering digunakan dalam berbagai kegiatan, baik masyarakat
benar-benar terlibat secara aktif atau hanya sebagai pendengar dan penggembira saja.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 63
Partisipasi masyarakat memiliki beberapa tingkatan, mulai dari yang terendah sampai
yang tertinggi sebagai berikut:
1. Masyarakat hanya menerima informasi; keterlibatan masyarakat hanya sampai
diberi informasi (misalnya melalui pengumuman). Bagaimana informasi itu diberikan
ditentukan oleh si pemberi informasi (pihak tertentu).
2. Masyarakat mulai diajak untuk berunding; Pada tingkatan ini sudah ada
komunikasi dua arah, dimana masyarakat mulai diajak untuk diskusi atau berunding.
Pada tingkatan ini, meskipun masyarakat sudah dilibatkan dalam suatu perundingan,
pembuat keputusan adalah orang luar atau orang-orang tertentu.
3. Membuat keputusan secara bersama-sama antara masyarakat dan pihak luar.
Pada tahapan ini masyarakat sudah dilibatkan dalam memutuskan sebuah
kegiatan/program, namun dalam pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan
pengembangan masih dilakukan oleh pihak luar.
4. Masyarakat memiliki wewenang untuk mengatur sumber daya dan membuat
keputusan. Pada tahapan ini masyarakat terlibat secara keseluruhan, yaitu mulai
dari melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantau dan evaluasi sampai pada
tahap perluasan dan pengembangan.
Dari keempat tingkatan partisipasi tersebut, yang diperlukan dalam STBM Stunting
adalah tingkat partisipasi tertinggi dimana masyarakat tidak hanya diberi informasi,
tidak hanya diajak berunding tetapi sudah terlibat secara aktif dan mandiri.
POKOK BAHASAN 2: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM STBM-
STUNTING
A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai segala upaya fasilitasi yang bersifat
non-instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar
mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan,
dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan proses aktif yang berjalan resiprokal atau dua
arah. Masyarakat yang berdaya dalam bidang kesehatan berperan aktif dalam kegiatan
dan program kesehatan, sementara pemerintah atau fasilitator memberikan respon dan
mengakomodasi masukan dan permintaan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan
pembinaannya, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan diarahkan pada: 1)
pemberdayaan aparat agar lebih mampu, responsif, dan akomodatif, dan 2)
pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih mampu, proaktif, dan aspiratif.
Pemberdayaan masyarakat di dalam STBM-Stunting diharapkan dapat menciptakan
masyarakat yang mandiri dan memiliki kewenangan penuh untuk terlibat secara
keseluruhan dalam kegiatan mereka, mulai dari identifikasi dan analisis masalah,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pengembangan.
B. Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
1. Kesukarelaan, yaitu keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan
harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan
memecahkan masalah kehidupan yang dirasakan.
2. Otonom, yaitu kemampuan untuk mandiri atau melepaskan diri dari
ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun
kelembagaan yang lain.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 64
3. Keswadayaan, yaitu kemampuan untuk merumuskan, melaksanakan kegiatan
dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan
dukungan/ bantuan pihak luar.
4. Partisipatif, yaitu keikutsertaan semua pemangku kepentingan sejak
pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pemanfaatan hasil-hasil kegiatan dan pengembangannya.
5. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan
yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa
direndahkan.
6. Demokratis, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan
pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara
sesama pemangku kepentingan.
7. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling
memperdulikan.
8. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu, dan
mengembangkan sinergisme.
9. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi
oleh siapapun.
10. Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom
(kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumber daya kesehatan bagi
sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan
kesehatan.
Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan juga dilandaskan pada:
1. Prinsip-prinsip menghargai yang lokal, yang mencakup: pengetahuan lokal,
keterampilan lokal, budaya lokal, proses lokal, dan sumber daya lokal.
2. Prinsip-prinsip ekologi, yang meliputi: keterkaitan, keberagaman, keseimbangan,
dan keberlanjutan.
3. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan Hak Azazi Manusia, yang tidak merugikan
dan senantiasa memberikan manfaat kepada semua pihak.
C. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat mau berubah ke arah perilaku
yang lebih baik dan berdaya. Berdasarkan tahapannya, pemberdayaan masyarakat
dilakukan sebagai berikut:
- Diawali dengan pemberian informasi kepada masyarakat (individu, keluarga,
kelompok) secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan
masyarakat,
- memfasilitasi masyarakat agar dapat berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau
sadar (aspek pengetahuan atau knowledge),
- dari tahu menjadi mau (aspek sikap atau attitude),
- dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek
tindakan atau practice).
Untuk melaksanakan tahapan tersebut, diperlukan strategi. Strategi pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan mencakup:
1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan masyarakat
sehingga masyarakat mempunyai peluang yang sebesar-besarnya untuk terlibat
aktif dalam proses pembangunan kesehatan.
2. Pengembangan/pengorganisasian masyarakat dalam pemberdayaan dengan
mengupayakan peran organisasi masyarakat lokal makin berfungsi dalam
pembangunan kesehatan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 65
3. Peningkatan upaya advokasi yang mendukung masyarakat memperjuangkan
kepentingannya melalui pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
4. Penggalangan kemitraan dan partisipasi lintas sektor terkait, swasta, dunia
usaha dan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembinaan
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
5. Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan
lokal, baik dana dan tenaga serta budaya.
Contoh Pemberdayaan Masyarakat Bidang STBM-Stunting
Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dilakukan melalui
kegiatan musyawarah masyarakat desa (MMD). MMD adalah pertemuan seluruh warga
desa untuk membahas hasil Survei Mawas Diri (SMD) dan merencanakan
penanggulangan masalah kesehatan seperti sanitasi, air minum, dan stunting. MMD
bertujuan agar:
a. Masyarakat mengenal masalah sanitasi, air minum, dan stunting di wilayahnya.
b. Masyarakat sepakat untuk menanggulangi masalah kesehatannya.
c. Masyarakat menyusun rencana kerja untuk menanggulangi masalah sanitasi, air
minum, dan stunting.
MMD dilakukan secara bertahap, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Melakukan analisa situasi dengan melakukan telaah posyandu dan Survei Mawas
Diri (SMD).
b. Merencanakan pelaksanaan MMD.
c. Melakukan evaluasi MMD.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MMD adalah:
a. MMD harus dihadiri oleh pemuka masyarakat desa, petugas puskesmas, dan sektor
terkait di kecamatan (seksi pemerintahan dan pembangunan, BKKBN, pertanian,
agama, BPSPAMS/ Kelompok masyarakat penyedia air minum, kader, dan lain-lain).
b. MMD dilaksanakan di balai desa atau tempat pertemuan lainnya yang ada di desa.
c. MMD dilaksanakan segera setelah survei mawas diri (SMD) dilakukan.
Cara melakukan MMD adalah sebagai berikut:
a. Pembukaan dengan menguraikan maksud dan tujuan MMD dipimpin oleh Kepala
Desa.
b. Pengenalan masalah kesehatan, khususnya sanitasi, air minum, dan stunting oleh
masyarakat sendiri melalui curah pendapat dengan mempergunakan alat peraga,
poster, dan lain-lain dengan dipimpin oleh kepala desa.
c. Penyajian hasil SMD oleh kelompok SMD.
d. Perumusan dan penentuan prioritas masalah sanitasi, air minum, dan stunting atas
dasar pengenalan masalah dan hasil SMD, dilanjutkan dengan rekomendasi teknis
dari petugas kesehatan di desa atau perawat komunitas.
e. Penyusunan rencana penanggulangan masalah sanitasi, air minum, dan stunting
dipimpin oleh kepala desa.
f. Penutup.
D. Penerapan Pemberdayaan Masyarakat dalam STBM-Stunting.
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, termasuk diantaranya STBM-stunting,
mencakup beberapa kegiatan:
1. Upaya membangun kesadaran kritis masyarakat, dimana masyarakat diajak
untuk berfikir dan menyadari hak dan kewajibannya di bidang kesehatan.
Membangun kesadaran masyarakat merupakan awal dari kegiatan pengorganisasian
masyarakat yang dilakukan dengan membahas bersama tentang harapan mereka,
berdasarkan prioritas masalah kesehatan sesuai dengan sumber daya yang mereka
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 66
miliki. Sebagai contoh bila di suatu wilayah terdapat anak balita terutama anak di
bawah 2 tahun yang panjang badan atau tinggi badannya lebih rendah dibanding
teman sebayanya maka diharapkan keluarga dan masyarakat peduli dan kritis
bahwa anak tersebut mempunyai masalah gizi khususnya sunting. Masyarakat
diharapkan menyadari akan adanya stunting pada balita.
2. Perencanaan partisipatif, merupakan proses untuk mengidentifikasi masalah
kesehatan serta potensi untuk selanjutnya menterjemahkan tujuan ke dalam
kegiatan nyata dan spesifik yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam
perencanaan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan sendiri oleh masyarakat didampingi
oleh fasilitator. Hal ini selain dapat menimbulkan rasa percaya akan hasil
perencanaan juga membuat masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap kegiatan
yang dilakukan. Perencanaan partisipatif ini berbasis pada hasil survei dan
pemetaan mengenai potensi, baik kondisi fisik lingkungan dan sosial masyarakat,
yang digali sendiri oleh masyarakat. Dalam merencanaan kegiatan bagi anak yang
stunting maka masyarakat memulai dengan identifikasi besarnya masalah stunting
yang terjadi di masyarakat berdasarkan laporan atau pengamatan (screening).
Selanjutnya masyarakat membuat perencanaan kegiatan dengan mulai menetapkan
tujuan kegiatan dalam mengatasi masalah stunting.
3. Pengorganisasian masyarakat sendiri merupakan proses yang mengarah pada
terbentuknya kader masyarakat yang bersama masyarakat dan fasilitator berperan
aktif dalam lembaga berbasis masyarakat (contohnya: Forum Masyarakat Desa,
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, atau Kelompok-Kelompok Masyarakat
lainnya) sebagai perwakilan masyarakat yang berperan sebagai penggerak
masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan.
4. Monitoring dan evaluasi, dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pengelola
pemberdayaan dengan menggunakan metode dan waktu yang disepakati bersama
secara berkesinambungan untuk mengetahui dan menilai pencapaian kegiatan yang
dijalankan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kegiatan
yang berkelanjutan. Dalam kegiatan monitoring ini, masyarakat akan terus menerus
terlibat dalam kegiatan monitoring mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga
evaluasi kegiatan.
Di dalam STBM Stunting, pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menyasar 8 pilar
STBM-stunting, yaitu:
1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT)
4. Pengelolaa Sampah Rumah Tangga (PSRT)
5. Pengelolaan Limbah Cair Ruah Tangga (PLCRT)
6. Gizi Ibu Hamil
7. Pemberian Makan Bayi dan Anak, dan
8. Pemantauan Pertumbuhan.
Dalam praktiknya di masyarakat, diharapkan kedelapan pilar ini dapat dilakukan secara
menyeluruh atau terintegrasi.
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan ketika melakukan MMD untuk isu
terkait STBM-stunting:
Pembukaan, dengan menjelaskan maksud MMD untuk membahas isu-isu terkait
sanitasi dan gizi, khususnya stunting.
Pengenalan masalah kesehatan dengan:
a. Menjelaskan informasi keadaan gizi dan kesehatan balita di desa tersebut,
terutama terkait besaran masalah gizi.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 67
b. Menyampaikan hasil SMD terkait gizi dan sanitasi/STBM.
c. Jika diperlukan, mintalah tenaga kesehatan untuk menjelaskan tentang isu
stunting (apa itu stunting, penyebab, solusi, dan lain-lain).
Pencarian solusi:
a. Memicu masyarakat untuk menyadari dan menyepakati bahwa masalah
stunting merupakan masalah bersama mengingat dampaknya yang sangat
besar bagi anak, keluarga, masyarakat, maupun negara.
b. Menanyakan tanggapan dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan
masalah tersebut. Sebagai contoh, jika masyarakat ingin agar semua balita
di desa berada pada pita hijau, fasilitator dapat membantu mengarahkan
diskusi kepada kegiatan-kegiatan memperbaiki, mempertahankan, dan
mencegah stunting.
Penentuan rencana tindak lanjut:
a. Menggali dari masyarakat tentang rencana tindak lanjut untuk menemukan
strategi dan perilaku keluarga dan masyarakat yang diharapkan agar tujuan
tercapai.
b. Mengajak dan memastikan masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan
yang disepakati.
c. Mendapatkan kesepakatan/komitmen pelaksanaan upaya perbaikan gizi dan
peningkatan kualitas sanitasi.
d. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran upaya tersebut.
Monitoring dan evaluasi kegiatan MMD
a. Melakukan evaluasi terhadap peran fasilitator MMD, pelaksanaan MMD, dan
hasil MMD.
b. Evaluasi terhadap peran fasilitator meliputi: materi yag disampaikan,
ketepatan waktu, metode dan sarana yang digunakan, pencapaian tujuan,
teknik pendalaman, dan isyarat dan reaksi terhadap masyarakat ketika
melakukan presentasi.
c. Evaluasi pelaksanaan MMD mencakup: jumlah peserta dan komposisi
masyarakat, tempat (kapasitas ruangan, kenyamanan), dan tingkat
partisipasi peserta/ respon peserta.
d. Evaluasi hasil MMD: identifikasi kontribusi yang diberikan masyarakat,
identifikasi perilaku unik/khusus, persetujuan perencanaan kegiatan, dan
evaluasi tindak lanjut setelah MMD.
VIII. REFERENSI
Permenkes No. 65/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
Permenkes No.3/2014 tentang STBM.
Kurikulum dan Modul Pelatihan Fasilitator STBM 2014.
Health Promotion and Community Participation, WHO, 2002.
IX. LAMPIRAN (Terlampir)
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 68
MODUL MI.3
KOMUNIKASI, ADVOKASI, DAN FASILITASI STBM-STUNTING
I. DESKRIPSI SINGKAT
Keberhasilan STBM dan penurunan stunting ditentukan oleh perubahan perilaku
masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, akses air minum aman
dan sanitasi layak, dan asupan nutrisi secara langsung. Untuk itu diperlukan fasilitator-
fasilitator yang terampil, khususnya dalam berkomunikasi, melakukan advokasi, dan
memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat.
Komunikasi merupakan proses pertukaran pendapat, pemikiran atau informasi, melalui
ucapan, tulisan, maupun tanda-tanda yang dapat mencakup segala bentuk interaksi
dengan orang lain. Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana
untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak terkait (stakeholders). Fasilitasi
adalah proses sadar untuk membantu sebuah kelompok mengambil keputusan secara
mandiri sehingga dapat berhasil melaksanakan tugas mereka sambil tetap menjaga
eksistensi kelompok tersebut.
Modul komunikasi, advokasi, dan fasilitasi ini disusun untuk memberikan pemahaman
dan keterampilan kepada para pelaksana STBM-Stunting dalam menjalankan perannya
secara utuh perannya sebagai fasilitator STBM-Stunting.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan komunikasi, advokasi, dan
fasilitasi STBM-Stunting.
B. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti materi ini peserta mampu:
1. Melakukan komunikasi STBM-Stunting,
2. Melakukan advokasi STBM-Stunting,
3. Melakukan fasilitasi STBM-Stunting.
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai berikut:
A. Pokok Bahasan 1: Komunikasi
1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Komunikasi
2. Komunikasi Efektif
3. Strategi Komunikasi STBM-Stunting
B. Pokok Bahasan 2: Advokasi
1. Pengertian advokasi
2. Cara Melakukan advokasi yang efektif
3. Langkah-langkah advokasi STBM-Stunting
C. Pokok Bahasan 3: Teknik Fasilitasi STBM-Stunting
1. Prinsip-prinsip fasilitasi STBM-Stunting
a. Pengertian fasilitasi
b. Prinsip dasar fasilitasi
c. Peran fasilitator
d. Perilaku fasilitator dalam STBM-Stunting
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 69
2. Teknik-Teknik Fasilitasi
1. Teknik mendengar
2. Teknik bertanya
3. Teknik menghadapi situasi sulit
4. Dinamika bertanya
5. Curah pendapat
IV. METODE PEMBELAJARAN
Ceramah Tanya Jawab, curah pendapat, diskusi kelompok, bermain peran, dan praktik.
V. MEDIA DAN ALAT BANTU
Bahan tayang (slide PPT), LCD, komputer/laptop, kain tempel, meta plan, spidol,
flipchart, modul, panduan diskusi kelompok, panduan bermain peran, dan panduan
praktik.
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Jumlah jam pelajaran yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 8 jam
pelajaran (T=2 jp, P=6 jp, PL=0 jp) @45 menit. Untuk mempermudah proses
pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh perserta, dilakukan langkah-
langkah kegiatan sebagai berikut:
Langkah 1: Pengkondisian (15 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Melakukan perkenalan (jika fasilitator pertama kali masuk ke kelas ini) dan bina
suasana serta salam menyapa peserta dengan ramah dan hangat.
b. Mengkaitkan dengan materi sebelumnya.
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan, dan metode yang
digunakan.
d. Melakukan curah pendapat dengan pertanyaan kunci “jika mendengar kata
KOMUNIKASI-ADVOKASI-FASILITASI, apa yang Bapak/Ibu pikir yang ada
dibalik kata-kata tersebut. Minta peserta menulis singkat maksimum 5 kata
dalam 1 kartu metaplan berbeda untuk komunikasi, advokasi, dan fasilitasi.
e. Mengelompokkan jawaban peserta dengan cepat dan menempelkan di kain.
2. Kegiatan Peserta
a. Menjawab salam dan mengikuti proses bina suasana.
b. Menyiapkan alat tulis bila diperlukan.
c. Memperhatikan penjelasan Fasilitator.
d. Memberikan jawaban dan atau menulis jawaban pada kartu meta plan atas
pertanyaan fasilitator dalam curah pendapat tentang Komunikasi, Advokasi dan
Fasilitasi.
Langkah 2: Penyampaian Pokok Bahasan (335 menit)
A. Pokok Bahasan 1: Komunikasi (75 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Mengkaitkan dengan hasil curah pendapat khsusnya tentang makna kata
komunikasi.
b. Memandu proses curah pendapat tentang pengertian komunikasi dan
memberikan rangkuman pengertian komunikasi.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 70
c. Meminta peserta berbagi ke dalam 2 kelompok. Bagikan Lembar Penugasan
(LP 3.1), minta setiap kelompok mengerjakan tugas sesuai LP 3.1. dalam waktu
10 menit (diskusi 5 menit dan peragaan/bermain peran 5 menit).
d. Memberikan penegasan tentang bentuk-bentuk komunikasi.
e. Meminta peserta untuk berkelompok menjadi 6 kelompok.
f. Membagikan Lembar Penugasan (LP 3.2.) “Diskusi Kelompok Menyusun Materi
Komunikasi Perubahan Perilaku”.
g. Memberikan rangkuman tentang SPB Komunikasi.
2. Kegiatan Peserta
a. Menjawab pertanyaan fasilitator terkait dengan pengertian komunikasi.
b. Membentuk menjadi 2 kelompok.
c. Mempelajari lembar penugasan LP 3.1, dan mengerjakan sesuai tugas yang
diberikan seperti dalam lembar tersebut.
d. Membentuk menjadi 6 kelompok
e. Mempelajari lembar penugasan LP 3.2 dan mengerjakan sesuai tugas yang
tertulis dalam lembar tersebut.
f. Menyimak rangkuman tentang Komunikasi.
B. Pokok Bahasan 2: Advokasi STBM-Stunting (60 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Mengkaitkan dengan hasil curah pendapat sebelumnya.
b. Menyampaikan pengertian dan menjelaskan langkah-langkah advokasi sambil
melakukan tanya jawab.
c. Menjelaskan bahwa untuk membahas cara melakukan advokasi, akan dilakukan
melalui diskusi kelompok dan bermain peran.
d. Membagi peserta ke dalam 3 kelompok (atau setiap kelompok beranggota 7-8
orang) dan tergantung jumlah stakeholders yang akan diadvokasi.
e. Membagikan lembar panduan diskusi kelompok dan Bermain Peran (LP 3.3)
kepada setiap kelompok.
f. Meminta setiap kelompok melakukan diskusi selama 20 menit tentang
Strategi/Cara dan Materi Advokasi sesuai lembar panduan.
g. Meminta setiap kelompok untuk bermain peran sesuai strategi
advokasinya/skenario yang sudah disusun sebelumnya dalam diskusi kelompok
(masing-masing selama 5 menit).
h. Setelah semua kelompok bermain peran dalam menjalankan strategi
advokasinya, fasilitator menanyakan, “Apa yang dipelajari dari proses bermain
peran tadi tentang strategi advokasi?” Jawaban ditulis dalam kertas flipchart.
i. Menjelaskan strategi dan langkah-langkah utama advokasi STBM-Stunting.
2. Kegiatan Peserta
a. Menyimak atau mendengarkan penjelasan keterkaitan antara materi ini dengan
hasil curah pendapat sebelumnya.
b. Memperhatikan penjelasan pengertian dan langkah-langkah advokasi serta
menjawab pertanyaan fasilitator.
c. Memperhatikan penjelasan proses diskusi.
d. Membentuk menjadi 4 kelompok.
e. Mempelajari panduan diskusi yang dibagikan fasilitator.
f. Melakukan diskusi kelompok sesuai dengan panduan diskusi selama 20 menit
dan menuliskan hasil diskusi dalam kertas flipchart.
g. Melakukan permainan peran sesuai skenario kelompok (masing-masing selama
5 menit).
h. Menjawab pertanyaan fasilitator berkaitan dengan pengalaman dalam bermain
peran.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 71
i. Menyimak penjelasan strategi dan langkah-langkah utama advokasi STBM-
Stunting.
C. Pokok Bahasan 3: Teknik Fasilitasi STBM-Stunting (200 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Mengkaitkan dengan hasil curah pendapat sebelumnya tentang fasilitasi,
menjelaskan pengertian fasilitasi, prinsip dasar fasilitasi, peran dan tugas
fasilitator sambil melakukan curah pendapat dan tanya jawab.
b. Menjelaskan bahwa “Perubahan Sikap, Perilaku dan Kebiasaan Fasilitator”
menjadi kunci dalam menjalankan peran-peran sebagai fasilitator atau pemicuan
STBM Stunting. Membagi peserta ke dalam 3 kelompok campuran (Kelompok-1
PERSONAL, Kelompok-2 INSTITUSIONAL dan Kelompok-3 PROFESIONAL)
untuk mendiskusikan “pentingnya perubahan perilaku dengan topik “upper-
lower”. Bagikan Panduan Diskusi Kelompok dan Peragaan Bahasa Tubuh
“Perubahan Perilaku Fasilitator” seperti LP 3.4.
c. Memandu presentasi hasil diskusi kelompok untuk membahas tentang siapa
“upper” dan siap “lower”-nya dari ketiga kelompok dan mengembangkan diskusi
tentang “mengapa seseorang atau sesuatu dianggap “upper” dan yang lainnya
dianggap “lower”?”
d. Membangun kesepakatan di akhir diskusi bahwa dalam pendekatan STBM-
Stunting cara pandang tersebut harus diubah sehingga tidak ada pendapat
siapa upper dan siapa lower (tidak ada yang memposisikan dirinya sebagai
upper dan tidak ada pula pihak lain yang dipandang sebagai lower).
e. Pada saat kelompok akan memperagakan Bahasa Tubuh, Fasilitator
memberikan petunjuk secara terpisah (Klp-1 menggambarkan suatu kegiatan
top–down, Klp-2 partisipatif dan Klp-3 friendly). Skenario peragaan tersebut
hanya diketahui oleh kelompoknya masing-masing dan tidak diketahui oleh
kelompok lainnya (rahasia).
f. Setelah penampilan ke tiga kelompok, tanyakan kepada kelompok pengamat
“apa yang menjadi karakteristik dari bahasa tubuh yang ditampilkan tersebut?”
g. Menanyakan bahasa tubuh yang bagaimana yang sesuai untuk pendekatan
STBM-Stunting (didasarkan pada pemahaman bahwa tidak ada yang dianggap
upper dan lower).
h. Gunakan bahan dalam bahan dalam Uraian materi seperti pada gambar 17 dan
uraiannya untuk menjelaskan pentingnya perubahan perilaku fasilitator. Bahwa
Proses Berbagi/Sharing dan Penerapan Metode akan terjadi dengan baik jika
sudah terjadi Perubahan Perilaku dan Kebiasaan Fasilitator baik dari sisi
Personal, Profesi dan Insitusi seperti tidak ada upper lower, sehingga terjadi
proses partisipatif dan friendly.
i. Membagi peserta menjadi 2 kelompok dan mengajak untuk melakukan role
play/bermain peran dalam rangka memahami bagaimana peran fasilitator yang
sebenarnya. Bagikan dan minta menggunakan Panduan Role Play/bermain
peran seperti LP 3.5. Berikan penjelasan secara terpisah untuk 2 kelompok
tersebut (Kelompok-1 sebagai FASILITATOR DAN Kelompok-2 sebagai GURU).
j. Setelah bermain peran, lakukan curah pendapat tentang “Apa Peran
Fasilitator?”, “Apa perbedaan prinsip Fasilitator dan Guru?” Perjelas dengan
menggunakan jendela 4 peran fasilitator.
k. Selanjutnya peserta dibagi dalam 3 kelompok yang sama dengan kelompok
topik “upper-lower”. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan bentuk
intervensi yang sesuai dalam menghadapi situasi diskusi sulit dan penuh
hambatan, yang umumnya muncul ketika pemicuan STBM-Stunting. Bagikan
Panduan Diskusi Kelompok seperti LP 3.6.
l. Memandu pleno/presentasi secara bertahap, minta kelompok-1 memulai
membacakan Bentuk/Kemungkinan Intervensi untuk Tipe-1, kemudian tanyakan
kepada kelompok lain (2 dan 3) apakah ada yang berbeda?, minta membacakan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 72
apa yang berbeda untuk Tipe 1 tersebut. Kemudian lanjutan pada tipe-2 oleh
kelompok 2 dan tanyakan kepada kelompok 1 dan 3 “apakah ada yang
berbeda?” Begitu seterusnya sampai bentuk/kemungkinan intervensi hingga
tipe 7 disepakati bersama oleh ke-3 kelompok.
m. Jelaskan “tips untuk menyeimbangkan dinamika dan mengelola anggota
kelompok yang sulit” seperti dalam uraian materi.
n. Mengajak peserta untuk melakukan diskusi kelompok (3-5 orang per kelompok)
dan praktik bertanya. Gunakan Panduan Diskusi Kelompok dan Praktik bertanya
seperti LP 3.7.
o. Memberikan kesempatan kepada kelompok secara acak untuk mempraktikkan
bertanya berdasarkan kalimat pertanyaan yang dibuat.
p. Meminta peserta lain untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan tersebut.
Minta kelompok melakukan secara bergantian sehingga lebih dari 75 %
kelompok mengajukan pertanyaan baik untuk alasan tertentu maupun untuk
pertanyaan dari setiap elemen pemicuan.
q. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapi hasil
praktik bertanya yang dilakukan dan mengidentifikasi pembelajaran penting.
2. Kegiatan Peserta
a. Mencatat penjelasan fasilitator dan memberikan jawaban atas pertanyaan curah
pendapat.
b. Melakukan kegiatan sesuai panduan diskusi kelompok.
c. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan memberikan jawaban refleksi
pembelajaran berdasarkan pertanyaan Fasilitator.
d. Menyepakati bahwa dalam pendekatan STBM-Stunting cara pandang tersebut
harus diubah sehingga tidak ada pendapat siapa upper dan siapa lower (tidak
ada yang memposisikan dirinya sebagai upper dan tidak ada pula pihak lain
yang dipandang sebagai lower).
e. Memperhatikan petunjuk fasilitator tentang peragaan bahasa tubuh dan
memperagakan bahasa tubuh sesuai dengan yang ditugaskan.
f. Menebak karakteristik bahasa tubuh yang diperagakan oleh kelompok lainnya.
g. Menjawab bahasa tubuh yang sesuai untuk pendekatan STBM-Stunting.
h. Menyimak dan atau mencatat penjelasan Fasilitator.
i. Mendiskusikan bentuk intervensi yang sesuai dalam menghadapi situasi diskusi
sulit dan penuh hambatan.
j. Memaparkan hasil diskusi kelompok.
k. Menyimak penjelasan tentang tips menyeimbangkan dinamika dan mengelola
anggota kelompok yang sulit.
l. Memainkan peran sesuai yang diminta fasilitator dan panduan.
m. Memberikan pendapat tentang peran fasilitator dan perbedaan antar kedua
peran yang mainkan tersebut.
n. Melakukan praktik bertanya sesuai panduan.
o. Memberikan tanggapan dan komentar pembelajaran atas praktik sebelumnya.
Langkah 3: Kesimpulan (10 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Merangkum sesi pembelajaran bersama peserta.
b. Meminta komentar, penilaian, saran bahkan kritik dari peserta pada kertas
evaluasi yang telah disediakan.
c. Menutup sesi pembelajaran dengan memastikan TPU dan TPK telah tercapai
dengan permainan ‘bola api’, dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait
materi yang sudah diberikan.
2. Kegiatan Peserta
a. Merangkum sesi pembelajaran bersama fasilitator.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 73
b. Mencatat hal-hal yang dianggap penting.
c. Menjawab pertanyaan yang diajukan fasilitator.
VII. URAIAN MATERI
POKOK BAHASAN 1: KOMUNIKASI STBM-STUNTING
A. PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI
1. Pengertian Komunikasi
Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, pendapat, perasaan, atau
berita kepada orang lain. Komunikasi dapat pula diartikan sebagai proses
pertukaran pendapat, pemikiran atau informasi melalui ucapan, tulisan maupun
tanda-tanda. Dengan demikian maka komunikasi dapat mencakup segala bentuk
interaksi dengan orang lain.
2. Bentuk-Bentuk Komunikasi
a. Komunikasi Verbal
Sering disebut komunikasi lisan, sehingga komunikasi verbal adalah penyampaian
suatu informasi secara lisan, yang biasa dikenal dengan berbicara. Namun dalam
praktik sehari-hari, informasi juga disampaikan melalui tulisan. Meskipun dalam
bentuk tulisan, tetapi bahasa yang dipakai adalah bahasa lisan, sehingga
digolongkan ke dalam komunikasi verbal. Pengiriman SMS atau obrolan di media
sosial seperti what’s app, Line, facebookmerupakan salah satu contoh. Bahasa
yang digunakan adalah lisan, yang menunjukkan hubungan personal yang tinggi.
Contoh lainnya adalah media tulisan seperti
bulletin, pamflet, leaflet, dan sebagainya yang
juga bertutur menyampaikan maksud dan
tujuannya.
Dalam komunikasi lisan dan tatap muka (yang
umum digunakan dalam proses pemicuan
STBM-Stunting), maka “mendengarkan” adalah
cara untuk memahami pesan bagi komunikan
dan memahami umpan balik bagi komunikator.
Berbeda dengan komunikasi tertulis dimana
pemahaman bisa tercapai dengan membaca
ulang. Mendengarkan memerlukan perhatian
lebih karena pengulangan akan menyebabkan gangguan dalam komunikasi. Karena
itu, baik komunikator maupun komunikan perlu mendengarkan secara aktif,
sehingga pesan maupun umpan balik dapat dipahami dengan benar.
Keterampilan mendengarkan adalah keterampilan yang dapat dipelajari. Agar
mampu berkomunikasi dengan baik, maka kita perlu berlatih menggunakan
pendekatan mendengarkan yang sesuai dengan pendekatan komunikasi yang kita
hadapi. Misalnya, untuk komunikasi yang empatik, kita gunakan pendekatan
mendengarkan untuk empati. Untuk komunikasi persuasif, kita gunakan pendekatan
mendengarkan untuk kesepakatan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 74
b. Komunikasi Non Verbal
Adalah cara komunikasi atau menyampaikan pesan melalui beberapa cara selain
lisan dan tulisan, misalnya dengan cara berpakaian, waktu, tempat, isyarat
(gestures), gerak-gerik (movement), sesuatu barang, atau sesuatu yang dapat
menunjukkan suasana hati perasaan pada saat tertentu. Contoh komunikasi non
verbal:
1) Cara berpakaian; orang yang sedang berkabung karena kematian, biasanya
akan berpakaian hitam-hitam atau memasang tanda dengan kain hitam di
lengan bajunya. Seseorang yang biasanya berpakaian biasa-biasa saja tiba-tiba
berpakaian lengkap dengan jas dan dasi, ini tentu juga suatu informasi bahwa
yang bersangkutan mungkin sedang dalam suasana yang lain misalnya akan
dilantik menjadi pejabat, akan menghadiri pesta atau pertemuan yang penting
dan sebagainya.
2) Waktu; bunyi beduk atau lantunan suara azan di masjid atau mushola,
memberikan informasi bahwa waktu shalat telah tiba. Bunyi bel di sekolah yang
menunjukkan bahwa waktu masuk kelas, istirahat atau pulang telah tiba. Bunyi
kentongan kayu (umumnya terjadi di Bali), pertanda waktu untuk kegiatan
tertentu seperti gotong royong, rapat banjar dan lain sebagainya akan segera
dimulai.
3) Tempat; Pemimpin suatu pertemuan atau rapat biasanya duduk di depan atau di
kepala meja. Ini menginformasikan bahwa yang bersangkutan adalah pemimpin
rapat yang biasanya orang penting atau memiliki jabatan tertentu. Ruang kerja
kepala Puskesmas tentunya akan berbeda dengan ruang kerja juru imunisasi
demikian juga ruang kerja dan peralatannya.
4) Isyarat; Peserta di suatu seminar secara spontan bertepuk tangan dengan riuh
setelah mendengarkan paparan seseorang penyaji yang mempresentasikan
materinya dengan baik dan menarik. Tepuk tangan tersebut merupakan isyarat
bahwa peserta puas terhadap paparan penyaji tersebut. Sebaliknya, jika peserta
mulai menguap, atau keluar masuk kelas, atau ada yang berbisik-bisik ketika
fasilitator memberikan materi/ kuliah, ini suatu isyarat bahwa materi atau cara
membawakan materi tersebut kurang berkenan di hati peserta. Contoh lain
misalnya mengacungkan dua jari tanda victory (kemenangan), menggeleng
tanda tidak tahu, raut wajah yang asam tanda tidak senang, murung tanda
bersedih, tangan mengepal tanda marah, tatapan mata bisa bermacam arti dan
sebagainya.
B. KOMUNIKASI EFEKTIF, EMPATIK, DAN PERSUASIF
1. Komunikasi Efektif
Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami
pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan balik
yang sesuai dengan pesan. Umpan balik yang sesuai dengan pesan tidak selalu berupa
persetujuan. Komunikan dapat saja memberikan umpan balik berupa ketidaksetujuan
terhadap pesan, yang terpenting adalah dimengertinya pesan dengan benar oleh
komunikan dan komunikator memperoleh umpan balik yang menandakan bahwa
pesannya telah dimengerti oleh komunikan. Contoh, petugas puskesmas meminta data
stunting kepada kader posyandu. Kader mengerti permintaan petugas puskesmas,
tetapi tidak bisa memberikan data tersebut karena tidak tersedia, maka komunikasi
yang terjadi telah efektif. Komunikasi tersebut efektif, meskipun umpan balik tidak
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 75
sesuai keinginan petugas puskesmas, karena pesan telah dimengerti dengan benar dan
diberikan umpan balik.
Agar komunikasi efektif terjadi terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
a. Keselarasan elemen-elemen komunikasi dengan pesan. Elemen-elemen
komunikasi harus mendukung isi pesan. Elemen komunikasi tersebut adalah
komunikator, pesan, saluran, umpan balik, dan komunikannya. Komunikasi akan
efektif jika terdapat keselarasan isi pesan dengan elemen-elemen lain dari proses
komunikasi.
b. Minimalisasi hambatan komunikasi. Komunikasi akan efektif jika hambatan
berhasil diminimalkan. Hambatan komunikasi dapat terjadi pada tiap elemen
komunikasi termasuk pada situasi komunikasi.
Berikut ini ilustrasi ketika keselarasan elemen-elemen komunikasi tidak diperhatikan
yang mendorong komunikasi menjadi tidak efektif. Tenaga gizi di Puskesmasr
memerlukan data stunting di RT Segar. Untuk itu, dia meminta kader mengumpulkan
data di masyarakat.. Maka, kader tersebut mendatangi warga dan menanyakan kondisi
stunting kepada warga. Kader menyerahkan data kepada petugas puskesmas. Ketika
petugas membaca data yang diberikan, ternyata hanya berisi nama tetapi tidak berisi
umur dan panjang/tinggi anak. Komunikasi ini tidak efektif karena kader sebagai
komunikan tidak memahami pesan dengan benar. Hal ini disebabkan ketidakselarasan
elemen komunikator, yaitu kader dengan isi pesan.
2. Komunikasi Empatik
Komunikasi empatik adalah komunikasi yang
menunjukkan adanya saling pengertian antara
komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini
menciptakan interaksi yang membuat satu pihak
memahami sudut pandang pihak lainnya. Sebagai
contoh, tenaga gizi Puskesmas meminta kerjasama
dari kader berupa penyediaan data stunting secara
lengkap. Setelah berkomunikasi, akhirnya kader
memahami kebutuhan petugas puskesmas dan
mengerti bahwa tanpa bantuannya, maka petugas
puskesmas akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugas. Dalam kondisi ini,
kader telah berempati terhadap kebutuhan petugas puskesmas.
Komunikasi empatik bisa dipahami dari kata empati. Empati adalah kemampuan
seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu, dari sudut
pandang dan perspektif orang lain tersebut. Jadi komunikasi empatik dapat menjadi
sarana untuk menjalin saling pengertian antara dua pihak. Berkaitan dengan stunting,
komunikasi empatik dapat dijadikan sarana untuk menghapus salah persepsi kader atas
tujuan pendataan stunting. Kader sering mempersepsikan pekerjaan petugas
puskesmas sebagai pekerjaan yang menyusahkan. Jika petugas puskesmas berhasil
mengembangkan komunikasi empatik, maka diharapkan kader dapat memahami bahwa
tujuan utama dari pendataan adalah agar petugas puskesmas dan kader sama-sama
dapat menyelesaikan tugasnya secara lebih efektif.
Agar komunikasi empatik tercipta, maka komunikator harus memperlihatkan:
a. Ketertarikan terhadap sudut pandang komunikan. Sikap ini akan mendorong
komunikan untuk lebih terbuka.
b. Sikap sabar untuk tidak memotong pembicaraan. Banyak informasi yang didapat
jika komunikator bersabar untuk memeroleh penjelasan detail dari sudut pandang
komunikan. Jika informasi yang diperoleh telah cukup dan komunikan hanya
berputar-putar menjelaskan hal yang sama, maka komunikator perlu menyampaikan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 76
kembali pengertian yang telah didapatnya dan
menarik perhatian komunikan pada masalah
berikutnya.
c. Sikap tenang, meskipun menangkap ungkapan
emosi yang kuat. Beberapa sudut pandang
bersifat sangat pribadi, sehingga saat
mengungkapkannya keterlibatan emosi tidak dapat
dihindari. Sebagai contoh, komunikan
mengungkapkan kemarahannya saat menceritakan
ketidaksetujuannya terhadap suatu keputusan
rapat. Atau komunikan merasa malu pada saat
proses pemicuan STBM-Stunting.
d. Bersikap bebas prasangka, atau tidak evaluatif, kecuali jika sangat diperlukan.
Untuk dapat memahami sudut pandang orang lain, kita hindari sikap evaluatif. Sikap
evaluatif dapat membuat komunikan menyeleksi hal-hal yang perlu disampaikan dan
tidak, dengan pertimbangan apakah sudut pandangnya akan diterima atau tidak,
disetujui atau tidak, oleh komunikator. Jika ini terjadi, maka kita tidak dapat mengerti
sudut pandang komunikan dengan benar. Sikap evaluatif diperlukan ketika
komunikan mendesak komunikator untuk menilai pandangan komunikan.
e. Sikap awas pada isyarat permintaan pilihan atau saran. Sikap ini
memperlihatkan adanya dukungan atau bantuan yang bisa diharapkan komunikan
dari komunikator. Pemberian dukungan dan bantuan akan mengembangkan empati
pada diri kader, kesiapan untuk membalas dukungan dan bantuan yang diterimanya.
f. Sikap penuh pengertian. Sebagai contoh, komunikan mendesak untuk
memperoleh persetujuan dari komunikator atas sudut pandangnya. Komunikator
tidak setuju. Komunikator cukup menyatakan bahwa dia dapat mengerti sudut
pandang tersebut, tidak perlu menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya.
3. Komunikasi Persuasif.
Komunikasi persuasif dapat dilihat sebagai derajat interaksi yang lebih tinggi dibanding
komunikasi efektif dan empatik. Komunikasi persuasif bertujuan untuk membuat
komunikan memberikan umpan balik sesuai keinginan komunikator. Pengertian
persuasif sendiri adalah perubahan sikap akibat paparan informasi dari pihak lain.
Dalam audit, komunikasi persuasif banyak digunakan, mulai dari permintaan kesediaan
kader untuk membantu pendataan, hingga mendorong kader untuk melaksanakan
pemicuan.
Agar komunikasi persuasif terjadi, maka komunikator perlu mengembangkan
komunikasi efektif dan empatik. Komunikasi persuasif dapat dikembangkan melalui:
a. Kejelasan penyampaian pesan. Agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas,
maka perlu memperhatikan keselarasan elemen-elemen komunikasi dan
meminimalkan hambatan komunikasi.
b. Pemahaman sudut pandang dan keinginan komunikan. Komunikator dapat
meminta komunikan melakukan sesuatu sesuai keinginan komunikator, hanya jika,
komunikan melihat bahwa tindakan tersebut sesuai dengan keinginan si komunikan
sendiri. Untuk mengetahui sudut pandang komunikan dan keinginan auditan,
komunikasi empatik dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sebelum meningkatkannya
menjadi komunikasi persuasif.
Dari uraian tentang komunikasi persuasif, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
syarat komunikasi persuasif adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif
dan empatik. Komunikasi ini dapat dikembangkan jika petugas puskesmas dan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 77
kader memiliki keterampilan untuk menyusun dan menyampaikan pesan dalam
kode verbal dan nonverbal, serta keterampilan mendengarkan.
C. STRATEGI KOMUNIKASI STBM-STUNTING
1. Kenali siapa mitra bicara
Dalam berkomunikasi kita harus menyadari dengan siapa kita berbicara, apakah
dengan camat, lurah, bidan desa, tokoh masyarakat, atau kader kesehatan.
Kenapa kita harus mengetahui dengan siapa kita bicara? Karena dengan
mengetahui audience, kita akan menyesuaikan dalam memilih kata-kata yang
digunakan dalam penyampaian informasi/pesan. Kita harus memakai bahasa yang
sesuai dan mudah dipahami oleh audience kita.
Selain itu, pengetahuan mitra bicara kita juga harus diperhatikan. Informasi yang
ingin kita sampaikan mungkin bukan merupakan hal yang baru bagi mitra kita,
tetapi kalau penyampaiannya menggunakan istilah yang tidak dipahami oleh mitra
kita, informasi atau ide yang kita sampaikan bisa saja tidak dipahami oleh mitra.
Dengan memperhatikan mitra bicara, kita akan dapat menyesuaikan diri dalam
berkomunikasi dengannya.
2. Ketahui apa tujuan komunikasinya
Cara kita menyampaikan informasi sangat tergantung pada tujuan kita
berkomunikasi, misalnya;
- Fasilitator STBM-Stunting ingin menyampaikan informasi mengenai pelatihan
pembuatan sarana jamban dan CTPS di wilayah kecamatan A. Jika tujuannya
hanya menyampaikan informasi maka komunikasi dapat dilakukan dengan
membuat pengumuman atau surat edaran.
- Sebagian besar masyarakat di desa A masih BAB sembarangan, sehingga
angka diare dan angka stunting/orang pendek di desa A banyak. Untuk itu,
fasilitator mengusulkan dilakukan pemicuan. Bila tujuannya seperti itu, tentu
pendekatannya bukan dengan surat tetapi melalui advokasi dengan berbagai
media yang berisi angka-angka kejadian riil di desa tersebut.
- Masyarakat desa A yang sudah terpicu, ingin membuat jamban sehat, namun
mereka tidak memiliki cukup biaya untuk membayar pembangunan jamban
secara kontan. Mereka mampu membayar secara mencicil selama beberapa
waktu. Untuk kasus tersebut, tentunya melalui proses negosiasi dengan
penyedia jasa seperti wirausaha STBM-Stunting.
3. Ketahui dalam konteks apa komunikasi dilakukan
Dalam berkomunikasi maka kita perlu mempertimbangkan keadaan atau
lingkungan saat kita berkomunikasi. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus
sesuai dengan keadaan dan lingkungan dimana komunikasi itu terjadi. Bisa saja
kita menggunakan bahasa dan informasi yang jelas dan tepat tetapi karena
konteksnya tidak tepat, reaksi yang kita peroleh tidak sesuai dengan yang
diharapkan. Misalnya penggunaan kata “mendukung”:
- Kita harus mendukung pelaksanaan STBM-Stunting di desa/kelurahan kita.
- Pemuda itu mendukung nenek tua yang sakit itu
Penggunaan kata mendukung pada kedua kalimat tersebut konteksnya berbeda
satu sama lain.
4. Pahami kultur
Dalam berkomunikasi harus diingat peribahasa “dimana bumi dipijak, disitu langit
dijunjung” artinya dalam berkomunikasi harus memperhatikan dan menyesuaikan
diri dengan budaya atau kebiasaan orang atau masyarakat setempat. Misalnya
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 78
berbicara sambil menunjuk sesuatu dengan telunjuk kepada orang yang lebih tua
atau lebih tinggi kedudukannya di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah bisa
dianggap kurang sopan atau kurang ajar walaupun mungkin di daerah lain itu
biasa-biasa saja. Atau jika di daerah Sumatera Utara orang biasa berbicara dengan
intonasi dan nada suara yang keras, maka apakah orang non Sumatera Utara
harus mengimbangi pula dengan nada yang keras?. Dalam hal ini, misalnya orang
Sunda kalau berbicara dengan orang Batak tidak perlu bertutur seperti orang
Batak, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian maka tidak terjadi salah tafsir
yang mengakibatkan kegagalan komunikasi.
5. Pahami bahasa BATAS
Dalam berkomunikasi seyogyanya kita memahami bahasa mitra kita. Hal ini tidak
berarti kita harus memahami semua bahasa dari mitra bicara. Oleh karena ada
kata-kata yang menurut etnis tertentu merupakan hal yang lumrah tapi menurut
etnis lain merupakan hal yang tabu untuk dikatakan atau mempunyai arti yang
berbeda. Misalnya ucapan “nang tok” menurut bahasa Sunda berarti “nangka saja”,
tetapi untuk orang Jawa ini berarti lain. Begitu juga ”gedang” menurut orang Sunda
dan Bali artinya “papaya” tapi menurut orang Jawa artinya “pisang”. Untuk
memperjelas pesan yang hendak disampaikan dalam berkomunikasi, gunakanlah
kalimat-kalimat sederhana yang mudah dipahami. Kalimat panjang dan kompleks
seringkali mengaburkan arti dan makna pesan yang akan disampaikan. Misalnya
kepala Puskesmas, berbicara kepada para Sanitarian dan tenaga gizi dalam suatu
rapat “Bapak Ibu Sanitarian dan tenaga gizi sekalian dalam rangka mensukseskan
STBM-Stunting, maka semua Sanitarian harus menyadari akan arti pentingnya
pembangunan kesehatan dengan memberdayakan semua potensi yang ada dalam
masyarakat, untuk itu maka Bapak Ibu Sanitarian dan tenaga gizi harus berusaha
sekuat tenaga untuk membuat masyarakat berdaya dan mendukung STBM-
Stunting’’. Kalimat tersebut terlalu panjang dan kompleks, akan melahirkan
multitafsir dan banyak perintah yang kurang focus. Padahal informasi yang perlu
disampaikan adalah bahwa agar program sanitasi dan stunting yang menggunakan
pendekatan STBM dapat dilaksanakan dengan memberdayakan potensi yang ada
di masyarakat.
6. Pahami Ekspresi Wajah dan Bahasa Tubuh
Pesan dalam komunikasi menempati posisi sentral. Pesan tidak lain adalah
stimulus-stimulus informatif dari komunikator kepada komunikan. Stimulus ini
disampaikan dalam bentuk verbal dan nonverbal. Untuk menghasilkan stimulus
verbal yang informatif, maka kita perlu menyampaikan pesan secara sederhana,
ringkas, lengkap, dan sistematis. Dalam komunikasi tatap muka, pesan dalam
bentuk verbal tidak dapat dipisahkan dari pesan nonverbal yang disampaikan
melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Pemahaman atas ekspresi wajah dan
bahasa tubuh akan membantu komunikator untuk:
a. Menjaga keselarasan kode verbal dalam pesan dengan kode nonverbal
ekspresi wajah dan bahasa tubuh agar komunikasi efektif.
b. Memahami umpan balik komunikan.
c. Menilai kesesuaian kode verbal dan nonverbal komunikan untuk menentukan
validitas informasi.
Ekspresi wajah adalah gerakan wajah yang menyampaikan emosi dan sikap
tertentu. Emosi yang terlihat dari ekspresi wajah bersifat universal. Ekspresi wajah
bahagia dari orang Amerika akan sama dengan ekspresi wajah bahagia orang
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 79
Indonesia. Emosi-emosi yang dapat dikenali dari ekspresi wajah adalah:
Senang/Bahagia, Sedih, Marah, Tidak suka, Jijik, Takut, Terkejut.
Bahasa tubuh adalah gerakan-gerakan anggota tubuh yang merupakan
perwujudan dari “informasi dan perintah” otak. Gerakan-gerakan ini bersifat
spontan karena merupakan hasil belajar seseorang berdasarkan pengaruh-
pengaruh genetik dan kebudayaan. Berikut ini contoh-contoh sederhana bahasa
tubuh:
a. Kita mengangguk jika setuju.
b. Kita berjongkok karena ketakutan.
c. Kita tertunduk dan menggelengkan kepala saat merasa prihatin.
d. Kita membusungkan dada dan mencondongkan badan ke depan untuk
memberikan tantangan atau menyatakan siap menyambut tantangan.
Dalam mengembangkan konsep-konsep komunikasi untuk perubahan perilaku, maka
kita harus memahami proses perubahan perilaku umumnya. Proses pemahaman
tersebut harus mendasarkan pada hasil temuan yang selanjutnya dapat dikembangkan
ke dalam suatu strategi komunikasi. Adapun alur proses pengembangan media
komunikasi perubahan perilaku adalah seperti bagan berikut:
PENILAIAN MEDIA
Pelajari Perilaku Sasaran
UMPAN BALIK KOMUNIKASI
SURVEY dan ANALISA
PERUBAHAN
PERILAKU EFEKTIF
PENGEMBANGAN UJICOBA
MEDIA LAPANGAN
Konsisten – Bahasa Sederhana – Logo – Pesan – Sasaran – Fokus - Slogan
Gambar 14: Alur Proses Mengembangan Konsep-Konsep Komunikasi Perubahan Perilaku
POKOK BAHASAN 2: ADVOKASI STBM-STUNTING
A. Pengertian Advokasi
Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui macam-macam
bentuk komunikasi persuasif (JHU, 1999). Advokasi kesehatan dapat diartikan juga
sebagai suatu rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan
dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu maupun kelompok agar
pembuat keputusan membuat suatu kebijakan publik yang menguntungkan masyarakat.
Advocacy is a combination on individual and action to design to gain political
commitment, policy support, social acceptance and system support for particular health
goal programs (WHO, 1989).
Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan
komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (stakeholders). Berbeda dengan
bina suasana, advokasi diarahkan untuk menghasilkan dukungan berupa kebijakan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 80
(misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan), dana, sarana, dll.
Stakeholders yang dimaksud bisa tokoh masyarakat formal yang umumnya berperan
sebagai penentu kebijakan pemerintahan dan penyandang dana pemerintah juga dapat
berupa tokoh-tokoh masyarakat informal seperti tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain
yang umumnya dapat berperan sebagai penentu “kebijakan” (tidak tertulis) di
bidangnya. Selain itu, advokasi juga dapat dilakukan kepada tokoh-tokoh dunia usaha
yang diharapkan dapat berperan sebagai penyandang dana non-pemerintah.
Pada diri sasaran advokasi umumnya berlangsung tahapan-tahapan, yaitu (1)
mengetahui atau menyadari adanya masalah, (2) tertarik untuk ikut mengatasi masalah,
(3) peduli terhadap pemecahan masalah dengan mempertimbangkan berbagai alternatif
pemecahan masalah, (4) sepakat untuk memecahkan masalah dengan memilih salah
satu alternatif pemecahan masalah, dan (5) memutuskan tindak lanjut kesepakatan.
Dengan demikian, maka advokasi harus dilakukan secara terencana, cermat, dan tepat.
Bahan-bahan advokasi harus disiapkan dengan matang, yaitu:
1. Sesuai minat dan perhatian sasaran advokasi,
2. Memuat rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah,
3. Memuat peran si sasaran dalam pemecahan masalah,
4. Berdasarkan kepada fakta (evidence-based),
5. Dikemas secara menarik dan jelas,
6. Sesuai dengan waktu yang tersedia.
Advokasi akan lebih efektif bila dilaksanakan dengan prinsip kemitraan yaitu dengan
membentuk jejaring advokasi atau forum kerjasama.
B. Cara Melakukan Advokasi yang Efektif
1. Analisa Pemangku Kepentingan
Analisis pemangku kepentingan diperlukan karena sangat penting peranannya dalam
pengembangan rencana advokasi selanjutnya. Dalam analisis tersebut, setiap
pemangku kepentingan potensial dijajagi siapa dan seberapa besar peranannya dalam
isu yang akan diadvokasi.
Contoh Analisis Pemangku Kepentingan:
Pengambil Keputusan
Hal yang perlu diidentifikasi adalah:
Siapa, jumlah, lokasi, dan jenis kelamin.
Pengetahuan tentang masalah atau isu advokasi.
Saluran untuk mencapai pengambil keputusan.
Seberapa jauh pengaruhnya terhadap isi advokasi.
Apakah mendukung atau menentang masalah/isu advokasi dan alasannya.
Sekutu/mitra/teman
Hal yang perlu diidentifikasi adalah:
Siapa, jumlah, lokasi, dan jenis kelamin.
Pengetahuan tentang isu advokasi.
Jejaring kerja dan besarnya kelompok.
Kekuatan spesial seperti hubungan dengan media dan kemampuan
mobilisasi massa.
Pengalaman masa lalu di bidang advokasi.
Keinginan untuk membagi pengalaman keahlian dan sumber daya.
Harapan bergabung sebagai anggota sekutu.
Kelompok bertahan/menolak lawan
Hal yang perlu diidentifikasi adalah:
Siapa, jumlah, lokasi, dan jenis kelamin.
Pengetahuan tentang masalah atau isu advokasi.
Alasan bertahan/menentang.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 81
Bagaimana menjangkau kelompok oposisi.
Kepada siapa kelompok tersebut berkonsultasi dan melihat kelemahan dan
kekuatannya.
2. Strategi Advokasi
Adalah sebuah kombinasi dari pendekatan, teknik dan pesan-pesan yang diinginkan
oleh para perencana untuk mencapai maksud dan tujuan advokasi.
Langkah-langkah kunci dalam merumuskan strategi advokasi:
Mengidentifikasi dan menganalisa isu advokasi.
Mengidentifikasi dan menganalisa pemangku kepentingan utama.
Merumuskan tujuan yang terukur.
Mengembangkan pesan-pesan utama advokasi.
Mengembangkan strategi (pendekatan, teknik-teknik, pesan-pesan, dll).
Mengembangkan rencana aksi advokasi.
Merencanakan pengawasan, pemantauan, dan penilaian.
C. Langkah-Langkah Advokasi STBM-Stunting
1. Mendefinisikan isu strategis
Untuk melakukan advokasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan
atau mendefinisikan isu-isu strategis di suatu wilayah. Penetapan isu ini sangat penting
sebagai dasar untuk melakukan kebijakan.
Sebagai contoh, isu strategis di bidang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Stunting
adalah sebagai berikut:
“Empat puluh persen penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang
layak. Setiap tahun tercatat sekitar 121.100 kasus diare yang memakan korban lebih dari
50.000 jiwa akibat kondisi sanitasi yang buruk. Diare merupakan penyebab kematian balita
terbesar kedua di Indonesia. Selain kematian, buruknya sanitasi juga berpengaruh
terhadap pertumbuhan balita. Tahun 2013, terdapat 9 juta anak stunting, yang salah
satunya disebabkan karena kondisi sanitasi yang buruk. Akibat sanitasi yang buruk dan
stunting, pemerintah mengalami kerugian sebesar 5 Triliun per tahun (sekitar 2-3%
Pendapatan Domestik Bruto). Air limbah yang tidak diolah menghasilkan 6 juta ton kotoran
manusia per tahun yang dibuang langsung ke badan air, sehingga biaya pengolahan air
bersih menjadi semakin mahal. Untuk menanggulangi stunting dan berbagai masalah gizi
lainnya, pemerintah mengeluarkan 13 Triliun per tahun untuk membeli makanan tambahan,
sementara rumah tangga juga mengeluarkan banyak biaya untuk membeli makanan dan
pengobatan.
Setelah diterapkan isu-isu strategis, kemudian dilakukan inventarisasi pemangku
kepentingan, dan kemudian ditetapkan kegiatan-kegiatan advokasi yang perlu
dilakukan. Sebagai contoh, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2: Inventarisasi Pemangku Kepentingan dan Kegiatan Advokasi STBM-
Stunting
PEMANGKU
NO. ISU KEGIATAN ADVOKASI
KEPENTINGAN
1 Kurangnya Pemda, dinas Peningkatan kebijakan dan pendanaan
pengetahuan kesehatan, dinas untuk mendukung kegiatan PHBS dan
dan pendidikan dan penurunan angka Stunting.
kepedulian kebudayaan, TP Penelitian formatif mengenai perilaku
pada kondisi PKK, LSM, masyarakat dan strategi perubahan
PHBS dan orsosmas, toga / perilaku masyarakat yang berkelanjutan.
Stunting toma, media massa. Peningkatan ekspos media massa tentang
PHBS dan Stunting.
Pengkajian peraturan-perundang-
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 82
PEMANGKU
NO. ISU KEGIATAN ADVOKASI
KEPENTINGAN
undangan terkait dengan penerapan PHBS
dan Stunting.
2 Masyarakat Pemda,dinas Kajian mengenai jamban sehat (cost
tidak mampu kesehatan, dinas benefit analysis).
dalam pendidikan dan Peningkatan ekspos media massa tentang
penyediaan kebudayaan, TP cost benefit dan benchmarking penyediaan
jamban sehat PKK, LSM, jamban sehat.
orsosmas,
toga/toma, media
massa.
3. Perilaku ibu Pemda,dinas Kajian mengenai perilaku ibu dalam
kurang benar kesehatan, dinas memberi makan dan ASI.
dalam pendidikan dan Peningkatan ekspos media massa tentang
pemberian kebudayaan, TP dampak kognetif anak stanting
makan dan PKK, LSM,
ASI orsosmas,
toga/toma, media
massa.
Tabel 3: Pemilihan Isu Advokasi
NILAI (P)
NO KRITERIA UNTUK MEMILIH ISU
1 2 3
1 Isu yang mempengaruhi banyak orang
2 Isu yang mempengaruhi terhadap program kesehatan
3 Isu dengan misi/mandat organisasi
4 Isu dengan tujuan wawasan pembangunan kesehatan
5 Isu dapat dipertanggungjawabkan dengan intervensi advokasi
6 Isu dapat memobilisasi para mitra/pemangku kepentingan
Total Nilai
2. Menentukan Tujuan Advokasi
Tujuan adalah suatu pernyataan tentang suatu keadaan yang akan dicapai pada masa
tertentu. Dalam menetapkan tujuan advokasi lebih diarahkan pada perubahan perilaku
untuk meyakinkan para penentu kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, dalam menetapkan harus didahulukan dengan pertanyaan,
”Siapa yang diharapkan mencapai seberapa banyak dalam kondisi apa, berapa lama,
dan dimana?”
Jadi secara umum dapat dikatakan tujuan advokasi adalah:
Realistis, bukan angan-angan.
Jelas dan dapat diukur.
Isu yang akan disampaikan berdasarkan fakta (evidence based).
Siapa sasaran yang akan diadvokasi harus jelas.
Seberapa banyak perubahan yang diharapkan harus tertulis.
Penetapan tujuan advokasi sebagai dasar untuk merancang pesan dan media advokasi
dalam merancang evaluasi. Jika tujuan advokasi yang ditetapkan tidak jelas dan tidak
operasional maka pelaksanaan advokasi menjadi tidak fokus. Berikut adalah salah satu
contoh menetapkan tujuan mengenai pentingnya sanitasi yang layak untuk masyarakat.
Contoh menuliskan tujuan umum advokasi adalah:
Meningkatnya akses masyarakat perdesaan di Kabupaten Lebak atas jamban yang
layak dari 39% di tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2019.
3. Mengembangkan Pesan Advokasi
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 83
Pesan adalah terjemahan tujuan advokasi ke dalam ungkapan atau kata yang sesuai
untuk khalayak sasaran. Pengembangan pesan advokasi memerlukan perpaduan
kemampuan antara ilmu pengetahuan dan seni. Pesan advokasi mengajukan fakta dan
data akurat, juga diharuskan mampu untuk membangkitkan emosi dan kemampuan
seni untuk mempengaruhi para penentu kebijakan.
Efektivitas pesan (Seven C’s for Effective Communication)
Suatu pesan advokasi dapat dikatakan efektif dan kreatif jika memenuhi tujuh kriteria
sebagai berikut:
1) Command Attention
Kembangkan suatu isu atau ide yang merefleksikan desain suatu pesan. Bila terlalu
banyak ide akan membingungkan penentu kebijakan, sehingga mudah dilupakan.
2) Clarify the Message
Buatlah pesan advokasi yang mudah, sederhana dan jelas. Pesan yang efektif harus
memberikan informasi yang relevan dan baru bagi penentu kebijakan. Sebab bila
diremehkan oleh mereka secara otomatis pesan tersebut sudah gagal.
3) Create Trust
Pesan advokasi dapat dipercaya dengan menyajikan data dan fakta yang akurat.
4) Communicate the Benefit.
Tindakan yang dilakukan harus memberi keuntungan sehingga penentu kebijakan
merasa termotivasi untuk menerapkan kebijakan yang baru.
5) Consistency
Pesan advokasi harus konsisten. Artinya sampaikan suatu pesan utama di media apa
saja secara terus-menerus, baik melalui pertemuan, tatap muka, atau pun melalui
media.
6) Cather to the Heart and Head
Pesan advokasi harus bisa menyentuh akal dan rasa. Komunikasi yang efektif tidak
hanya memberikan alasan teknis, tetapi harus menyentuh nilai-nilai emosi dan
memangkitkan kebutuhan yang nyata.
7) Call to Action
Pesan advokasi harus dapat mendorong penentu kebijakan untuk bertindak atau
berbuat sesuatu. Kebijakan STBM yang dicanangkan oleh pemerintah, merupakan
suatu tindakan nyata untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap
jamban yang layak.
Pesan Advokasi
Merupakan pernyataan yang singkat, padat, dan bersifat membujuk.
Berhubungan dengan tujuan Anda dan menyimpulkan apa yang ingin Anda capai.
Bertujuan untuk menciptakan aksi yang Anda inginkan untuk dilakukan oleh
pendengar pesan Anda.
Gaya Pesan Advokasi
Seruan : Emosional vs Rasional
Seruan : Positif vs Negatif
Seruan : Masa vs Individu
Kesimpulan Tertutup vs Kesimpulan Terbuka
Pengemasan Pesan
Presentasi adalah kunci untuk menyampaikan pesan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 84
Sebuah presentasi yang berhasil adalah presentasi yang menarik, didukung oleh
fakta yang sahih dan tampilan yang menarik.
Pengemasan mencakup cetakan, materi audiovisual.
Dukungan kemasan dengan ilustrasi sederhana, grafik dan foto.
Dalam mengembangkan pesan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Pengemasan materi bagi kelompok sasaran berbeda.
Pesan bagi pembuat keputusan
Pesan bagi mitra dan sekutu
Masalah
Ukuran isu Pesan bagi keluarga yang
bertahan/menolak
Dampak
Pesan bagi masyarakat
Gambar 15: Pengemasan Materi Advokasi
b. Penggalangan sumberdaya termasuk dana.
Kenali dan coba dapatkan sumber daya (uang, tenaga, keahlian, jejaring, dan
perlengkapan lainnya) untuk melaksanakan kampanye advokasi.
c. Mengembangkan rencana kerja
Pelaksanaan rencana kegiatan advokasi sesuai dengan identifikasi kegiatan, tugas
pokok, dan fungsi dari para pelaksana, jangka waktu, serta sumber daya yang
dibutuhkan.
POKOK BAHASAN 3: TEKNIK FASILITASI STBM-STUNTING
A. Prinsip-Prinsip Fasilitasi STBM-Stunting
1. Pengertian Fasilitasi
Fasilitasi berasal dari kata facile (Perancis) dan facilis (Latin), yang artinya
mempermudah (to facilitate = to make easy). Fasilitasi diartikan sebagai proses
mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu atau bisa juga diartikan
melayani dan memperlancar suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Fasilitasi dapat
pula berarti: memungkinkan atau membuat mudah atau membantu orang agar dapat
memberdayakan diri mereka sendiri, hanya hadir disana, mendengarkan dan menjawab
kebutuhan orang-orang, atau memberikan dukungan kepada orang, kelompok dan
organisasi.
Fasilitasi adalah proses sadar untuk membantu suatu kelompok masyarakat sehingga
dapat berhasil melaksanakan tugas mereka sambil tetap menjaga eksistensi kelompok
itu.
Sedangkan orang yang mempermudah, melayani, dan memperlancar itu disebut
“Fasilitator”.
2. Prinsip Dasar Fasilitasi
Prinsip utama fasilitasi adalah proses, bukan isi. Seperti dijelaskan Hunter et al, (1993),
facilitation is about process – how you do something – rather than the content – what
you do. Facilitator is process guide; someone who makes a process easier or more
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 85
convenient to use. Artinya seorang fasilitator harus netral dan hanya berorientasi pada
proses bukan kepada isi dari sebuah diskusi.
Berikut tips untuk kesadaran diri sebagai fasilitator:
• Jangan menghakimi.
• Coba usahakan untuk tidak memproyeksikan persepsi Anda untuk orang lain.
• Jangan beranggapan bahwa orang lain membutuhkan bantuan Anda.
• Berkawanlah dengan jujur.
• Tunjukkan sikap hormat, dan hargai orang yang bekerja dengan Anda.
• Punyailah rasa percaya kepada orang yang bekerja untuk Anda.
• Terimalah bahwa orang mempunyai nilai, tingkah laku dan pandangan sendiri.
• Tunjukkan minat dalam seluruh aspek kehidupan manusia.
• Bertindaklah sebagaimana Anda harapkan orang lain bertindak untuk Anda.
• Jangan berpikir Anda mengerti lebih baik.
• Jangan memberi saran.
Selain tips di atas, hal yang dapat dikategorikan sebagai etika umum fasilitator dalam
fasilitasi seperti yang dikemukakan oleh Djohani (1996), antara lain:
1) Bersikap sabar
Aspek utama fasilitasi adalah proses belajar. Hal ini memerlukan kesabaran dan jika
tidak, berarti fasilitator telah mengambil kesempatan belajar mereka.
2) Mendengarkan dan tidak mendominasi
Karena proses berpusat pada masyarakat, maka fasilitator harus menjadi pemerhati
dan pendengar yang aktif. Seperti diungkapkan oleh Kaner (2007), Proses fasilitasi
adalah proses percakapan dan diskusi warga/anggota kelompok. Karenanya, fasilitator
bicara jauh lebih sedikit. Kecuali di bagian-bagian pengantar yang mungkin sedikit agak
panjang, fasilitator bicara tidak lebih dari 1½ menit. Fasilitator lebih banyak bertanya
dan bertanya hanya memakan waktu sekitar 10 detik. Bila dijumpai fasilitator yang
bicara panjang lebar, bahkan lebih panjang dari warga, maka patut diduga bahwa yang
terjadi bukanlah fasilitasi.
3) Menghargai dan rendah hati
Sering orang beranggapan masyarakat itu banyak ketidaktahuannya, miskin, dan
ketinggalan. Anggapan seperti itu harus dijauhkan dan mulai dengan pandangan positif.
Cara menghargai masyarakat adalah dengan menunjukan minat yang sungguh-
sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka.
4) Mau belajar
Seorang fasilitator untuk dapat memahami keadan masyarakatnya justru harus memiliki
semangat belajar. Di masyarakat banyak hal yang bisa dipelajari baik itu adat istiadat,
tata nilai dan norma-norma dari perkembangan masyarakat. Kita tidak akan bisa
bekerja sama dengan mereka apabila kita tidak tidak memhami atau belajar tentang
masyarakatnya.
5) Bersikap sederajat
Harus dihindari membandingkan keadaan masyarakat miskin dengan lingkungan yang
dianggap lebih maju. Sebaiknya dikembangkan sikap kesederajatan agar kita diterima
sebagai teman atau mitra kerja oleh masyarakat. Fasilitator tidak bersikap sebagai tamu
tapi harus menjadi bagian dari warga masyarakat yang bekerja langsung bersama
mereka.
6) Bersikap akrab dan melebur
Berinteraksi dengan masyarakat sebaiknya dilakukan secara informal, akrab dan santai,
sehingga kesederajatan pun tercipta. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak berpakaian
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 86
menyolok, saling berbagi makanan, tinggal bersama mereka, dan melakukan sendiri
keperluan-keperluan pribadi (mengambil air, mencuci dll).
7) Tidak menggurui
Proses belajar sementara fasilitator “gurunya” tapi hati hati untuk tidak bersikap
“menggurui”. Orang dewasa memiliki pengetahuan dan pengalaman serta konsep diri
karena itu tidak akan berhasil apabila kita bersikap sebagai “guru” yang serba tahu.
Sebaiknya kita belajar dengan saling berbagi pengalaman sehungga lebih banyak
pemahaman yang diperoleh.
8) Berwibawa
Meskipun suasana yang dibangun harus santai dan akrab, seorang fasilitator harus
tetap menunjukan kesungguh-sungguhan di dalam bekerja dengan masyarakat.
Dengan demikian masyarakat akan menghargainya.
9) Tidak memihak, menilai, dan mengeritik
Fasilitator harus tetap netral berfokus pada proses bukan pada substansi. Dalam proses
fasilitasi sering terjadi pertentangan, fasilitaor tidak boleh menilai dan mengeritik
pendapat pihak tertentu. Tetap netral dengan memfasilitasi komunikasi sehingga
diperoleh kesepakatan dan jalan keluarnya.
10) Bersikap terbuka
Suasana keterbukaan harus dibangun dengan luwes. Karena segan, malu atau takut
menyebabkan masyarakat enggan mengemukakan pendapat yang sebenarnya.
Masyarakat akan terbuka jika telah tumbuh kepercayaan kepada orang luar/ fasilitator.
Katakan tidak tahu kalau memang kita tidak tahu, itu jauh lebih baik dari pada pura-pura
tahu.
11) Bersikap positif
Selalu membangun suasana positif. Artinya kita mengajak masyarakat untuk memahami
keadaannya dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada, bukan sebaliknya
mengupas dan mengeluhkan kekurangan-kekurangan. Perlu diingat bahwa potensi
terbesar di masyarakat adalah kemauan dari manusianya sendiri untuk berubah.
3. Peran Fasilitator
Sesuai dengan semangat partisipatif, fasilitator mempunyai peran: (1) Sebagai
Katalisator (Catalyst), (2) Sebagai Pemberi Bantuan dalam Proses (Process Helper), (3)
Sebagai Pengubung dengan Sumber Daya (Resource Linker), (4) Sebagai Pemandu
Masyarakat untuk Menemukan Solusi, (5) Sebagai Pendamping dalam Proses
Pemantauan dan Evaluasi.
Kekuatan Seorang Fasilitator yang baik
Karakter utama seorang fasilitator yang baik adalah ia bersikap netral pada subtansi
(content neutral). Content neutral berarti ia tidak mengambil posisi pada isu yang
sedang dibicarakan dan tidak memiliki kepentingan pada hasil yang dicapai dari proses
diskusi tersebut.
Peran utama seorang fasilitator adalah menjadi pemandu proses (process guide). Ia
selalu mencoba proses yang terbuka, inklusif, dan adil sehingga setiap individu
berpartisipasi secara seimbang dan membangun ruang sama supaya semua pihak bisa
sungguh-sungguh berpartisipasi.
“Kekuatan seorang fasilitator adalah menjadi Content neutral dan process guide”
Kotak berikut menggambarkan peran fasilitator dapat dibedakan dari peran penyuluh,
narasumber, atau pengamat.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 87
Fasilitator Penyuluh
Questions/Bertanya
(bisa membantu formulasi (memberi saran jika
pilihan bila diminta) diminta)
Pengamat Narasumber
(bisa memberikan umpan balik (menyediakan solusinya
Asking
bila diminta) sendiri)
Menjelaskan/Telling
Gambar 16: Peran Fasilitator
Tujuan dan Tantangan Menjadi Content Neutral
Mengapa penting menjadi content neutral? Jika anda menfasilitasi hendaknya tidak
memberikan nasehat khususnya jika tidak benar-benar diminta. Bahkan bila diminta
pun, Anda jangan sering-sering membantu. Nasehat adalah telling kepada kelompok
apa yang Anda pikir hendaknya (atau sebaiknya) mereka Lakukan. Ini Berangkat dari
nilai-nilai yang Anda pikir lebih baik. Nasehat Anda Berarti mengabaikan bahwa setiap
orang itu berbeda. Pengalaman mereka berbeda-beda karena setiap keputusan yang
mereka ambil pasti selalu berbeda-beda.
Apa Tantangan menjadi content neutral? Apa Yang Anda Lakukan Saat Anda diminta
memberikan nasehat sebagai seorang fasilitator? Anda dapat menggunakan beberapa
contoh tanggapan atau pertanyaan tidak langsung yang disenaraikan sebagai berikut
ini:
Apa ada pilihan–pilihan lain atau alternatif yang bisa Anda pikirkan?
Apa keuntungan dan kelemahan pilihan-pilihan ini, menurut pendapat Anda?
Saya menyarankan Anda Menjawab pertanyaan itu untuk Anda Pribadi?
Apakah Anda ingin kelompok membuat beberapa saran?
Apa Anda Minta opini saya?
Tujuan dan Tantangan menjadi Pemandu Proses
Mengapa peran sebagai pemandu proses penting?
Kebanyakan kelompok memiliki kecenderungan pada substansi dan hasil. Karena itulah
mereka mau berkumpul bersama. Bagaimanapun jika kegiatan itu tidak rutin maka
kerapkali tidak memadai mencapai hasil yang diinginkan. Kebanyakan kelompok tidak
menyadari pentingnya proses. Mereka tidak tahu bagaimana cara memandu proses
atau mereka tidak pada posisi melakukan itu. Fasilitator, karena ia bersikap content
neutral, memiliki posisi mengelola proses. Fasilitasi adalah berbicara seni memobilisasi
kekuatan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
Apa Tantangan menjadi Pemandu proses?
Kebanyakan kelompok, dimana anda sering bekerja dengan mereka boleh jadi memiliki
pandangan berbeda tentang peran atau pekerjaan Anda sebagai fasilitator. Untuk itu
saat diminta membantu kelompok tersebut, Anda perlu melakukan beberapa hal berikut:
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 88
Kejelasan harapan anggota kelompok atas peran Anda.
Membuat pemahaman bersama tentang peran seorang fasilitator.
Kejelasan peran sebagai fasilitator.
Bagaimana keahlian yang dimiliki seorang fasilitator? Jika Anda tidak bisa membagi
pengetahuan kepada mereka, lantas bagaimana dengan keahlian atau kepakaran yang
Anda miliki? Adalah penting mengingatkan bahwa etika diatas tidak melarang sama
sekali. Anda membagi keahlian atau kepakaran yang Anda miliki kepada kelompok. Jika
ada sarjana ekonomi dan diminta kelompok menjelaskan tentang seluk beluk pasar
bebas atau globalisasi, Anda bisa berbagi pengetahuan dengan mereka.
4. Perilaku Fasilitator dalam STBM-Stunting
Tugas seorang fasilitator STBM-Stunting adalah memfasilitasi suatu proses pemicuan
agar terjadi perubahan perilaku masyarakat atas inisiatif masyarakat sendiri. Atas dasar
prinsip-prinsip dalam metode pemicuan STBM seperti pada uraian materi MI.1, maka
perilaku seorang fasilitator pemicu kepada masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan,
tidak ada yang dianggap lebih tinggi (upper) atau dianggap lebih rendah (lower).
Bahkan masyarakat sasaran adalah pihak yang lebih tahu tentang perilaku dan
kebiasaan yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun.
Untuk menggali dan mengidentifikasi bagaimana seharusnya sikap dan perilaku
seorang fasilitator pemicu pada saaat proses pemicuan, lakukan curah pendapat dan
diskusi secara partisipatif kepada semua peserta pelatihan. Tanyakan bagaimana sikap
kita saat berhadapan dengan orang yang lebih banyak tahu dibanding diri kita.
Hubungan antara seorang fasilitator dan masyarakat sasaran dapat diumpamakan
seperti sikap antara seorang murid (diri fasilitator) terhadap guru (masyarakat sasaran).
Jawaban peserta yang diharapkan muncul adalah bahwa perilaku seorang fasilitator
haruslah:
Penuh sopan santun dan hormat,
Banyak bertanya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan,
Selalu mendengarkan apapun informasi yang disampaikan masyarakat,
Bersikap kritis dan ingin menggali lebih dalam (misalnya tentang kenapa
masyarakat berperilaku buruk, dan apa sebenarnya pendapat masyarakat terhadap
perilaku buruknya),
Sabar dan tidak terburu-buru dalam memfasilitasi proses,
Tidak mengajari/tidak menggurui/tidak menyuruh ataupun manganjurkan sasaran
harus berbuat ini dan itu,
Tidak langsung menjawab terhadap pertanyaan masyarakat sasaran, tetapi
mengembalikan mereka untuk mencoba menjawabnya (tidak memberikan solusi.
Solusi ada pada masyarakat sendiri).
Dari berbagai informasi dan pendapat masyarakat, fasilitator kemudian meramu suatu
pertanyaan tentang apa yang akan diperbuat masyarakat ke depan untuk keluar dari
kondisi buruk/tidak nyaman seperti sekarang ini. Jawaban masyarakat akan menjadi
komitmen mereka tentang apa yang akan mereka lakukan (berubah perilaku), kapan
memulai dan bagaimana caranya.
Jika seorang calon fasilitator belum bersikap dan perilaku seperti di atas maka sangat
penting untuk memulai perubahan sikap dan perilaku dari sisi diri sendiri (sebagai
individu), juga dari sisi profesi dan dari sisi institusi. Jika perubahan sikap dan perilaku
seorang fasilitator sudah terjadi maka dia akan bisa berbagi (sharing) informasi dengan
masyarakat dan dapat berupaya untuk merubah perilaku masyarakat menggunakan
metode pemicuan yang ada. Hal di atas menjadi 3 pilar utama dalam pendekatan
partisipatif seperti tergambar dalam segitiga berikut:
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 89
Personal
Profesional Perilaku dan Institusional
kebiasaan
Proses Penerapan
Berbagi Metode
Gambar 17: Tiga Pilar Utama Perubahan Perilaku dalam Pendekatan Partisipatif
Ketiganya merupakan pilar utama yang harus diperhatikan dalam pendekatan CLTS,
namun dari ketiganya yang paling penting adalah “perubahan perilaku dan
kebiasaan” (Attitude and Behavior Change)”. Jika perilaku dan kebiasaan tidak
berubah maka kita tidak akan pernah mencapai tahap “berbagi (sharing)” dan sangat
sulit untuk menerapkan “metode” yang tepat.
Perubahan perilaku dan kebiasaan tersebut harus total, dimana didalamnya meliputi
perilaku personal atau individual, perilaku institusional atau kelembagaan dan perilaku
profesional atau yang berkaitan dengan profesi.
Salah satu perilaku dan kebiasaan yang harus berubah adalah perilaku fasilitator,
diantaranya:
Pandangan bahwa ada kelompok yang berada di tingkat atas (upper) dan kelompok
yang berada di tingkat bawah (lower). Cara pandang “upper-lower” harus dirubah
menjadi “pembelajaran bersama”, bahkan menempatkan masyarakat sebagai “guru”
karena masyarakat sendiri yang paling tahu apa yang terjadi dalam masyarakat itu.
Cara pikir bahwa kita datang bukan untuk “memberi” sesuatu tetapi “menolong”
masyarakat untuk menemukan sesuatu.
Bahasa tubuh (gesture); sangat berkaitan dengan pandangan upper lower. Bahasa
tubuh yang menunjukkan bahwa seorang fasilitator mempunyai pengetahuan atau
keterampilan yang lebih dibandingkan masyarakat, harus dihindari.
Ketika perilaku dan kebiasaan (termasuk cara berpikir dan bahasa tubuh) dari fasilitator
telah berubah maka “sharing” akan segera dimulai. Masyarakat akan merasa bebas
untuk mengatakan tentang apa yang terjadi di komunitasnya dan mereka mulai
merencanakan untuk melakukan sesuatu. Setelah masyarakat dapat berbagi, maka
metode mulai dapat diterapkan. Masyarakat secara bersama-sama melakukan analisa
terhadap kondisi dan masalah masyarakat tersebut.
Dalam STBM-Stunting fasilitator tidak memberikan solusi. Namun ketika metode telah
diterapkan (proses pemicuan telah dilakukan) dan masyarakat sudah terpicu sehingga
diantara mereka sudah ada keinginan untuk berubah tetapi masih ada kendala yang
mereka rasakan misalnya kendala teknis, ekonomi, budaya, dan lain-lain maka
fasilitator mulai memotivasi mereka untuk mecapai perubahan ke arah yang lebih baik,
misalnya dengan cara memberikan alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut.
Tentang usaha atau alternatif mana yang akan digunakan, semuanya harus
dikembalikan kepada masyarakat tersebut.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 90
Konsep-konsep inilah yang kemudian diadopsi oleh STBM-Stunting dan disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia. Konsep STBM-Stunting menekankan pada
upaya perubahan perilaku yang berkelanjutan untuk mencapai kondisi sanitasi total dan
menurunnya angka stunting melalui pemberdayaan masyarakat.
Fasilitasi yang Harus Dilakukan dan Dihindari dalam STBM-Stunting
Faktor penentu keberhasilan dan kegagalan (dapat diterapkan dan tidaknya) sangat
tergantung dari masyarakat. Meskipun bukan merupakan kesalahan fasilitator jika
masyarakat “menolak” untuk mengimplementasikan pendekatan STBM-Stunting dalam
komunitas mereka, namun peran fasilitator sangat berpengaruh. Sehingga, ada
beberapa hal yang harus dihindari oleh fasilitator dan beberapa hal yang sebaiknya
dilakukan saat memfasilitasi masyarakat, misalnya:
Tabel 4: Fasilitasi yang Harus Dilakukan dan Dihindari dalam STBM-Stunting
JANGAN LAKUKAN LAKUKAN
Menawarkan subsidi Memicu kegiatan setempat.
Dari awal katakan bahwa tidak akan pernah ada
subsidi dalam kegiatan ini. Jika masyarakat bersedia
maka kegiatan bisa dilanjutkan tetapi jika mereka tidak
bisa menerimanya, hentikan proses.
Mengajari Memfasilitasi
Menyuruh membuat Memfasilitasi masyarakat untuk menganalisa kondisi
jamban, sarana dan mereka termasuk gizi dan stunting, yang memicu rasa
prasarana sanitasi, atau jijik, malu, rasa takut dan mendorong orang dari BAB di
memperlihatkan contoh- sembarang tempat menjadi BAB di tempat yang tetap
contoh tipe jamban selama dan tertutup serta merubah perilaku sehat dan gizi
proses pemicuan seimbang.
Memberikan alat-alat atau Melibatkan masyarakat dalam setiap pengadaan alat
petunjuk kepada orang untuk proses fasilitasi.
perorangan
Menjadi pemimpin, Fasilitator hanya menyampaikan “ pertanyaan sebagai
mendominasi proses pancingan” dan biarkan masyarakat yang
diskusi. (Selalu berbicara/diskusi lebih banyak.
menunjukkan dan (Masyarakat yang memimpin).
menyuruh masyarakat
melakukan ini dan itu pada
saat fasilitasi)
Memberitahukan apa yang Membiarkan mereka menyadarinya sendiri
baik dan apa yang buruk
Langsung memberikan Kembalikan setiap pertanyaan dari masyarakat kepada
jawaban terhadap masyarakat itu sendiri, misalnya: “jadi bagaimana
pertanyaan-pertanyaan sebaiknya menurut bapak/ibu?”
masyarakat
B. Teknik-Teknik Fasilitasi
1. Teknik Mendengar
Apakah bedanya mendengar dan ”mendengarkan”? Apakah bedanya menggambar dan
”menggambarkan”? Mendengar yang pertama adalah memasukkan suara ke telinga,
sedangkan mendengar yang kedua (mendengarkan) adalah mengolah suara yang
masuk ke telinga menjadi lebih bermakna. Menggambar yang pertama adalah kerja
teknis tangan kita dengan pensil atau alat tulis di atas kertas, sedangkan
menggambar yang kedua adalah menggambarkan bentuk yang bermakna.
Untuk mendengar secara lebih bermakna, kita dibantu sejumlah pertanyaan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 91
Pertanyaan itu membuat kita lebih mengerti makna dari pernyataan atau ucapan dari si
pembicara. Ketika si pembicara mengatakan, ”Saya setuju bahwa”. Maka kita ajukan
pertanyaan, ”Apa yang Anda setuju tadi?”. Sehingga kita menjadi pendengar yang
lebih baik, atau mendorong orang lain untuk mendengar secara lebih baik.
Apabila terdapat peserta yang berbicara berputar- putar dan nampak tidak yakin
apakah penjelasannya ditangkap oleh pendengar sehingga mengulang-ulang dan
menjadi bingung sendiri, triks paraphrasing diperlukan untuk membantu si pembicara
memperjelas GAGASAN POKOK yang ingin disampaikannya. Itu juga berarti kita
mendengarkan si pembicara secara lebih baik dan membantu pendengar untuk
mendengarkan secara lebih baik.
Untuk peserta atau pembicara yang ’pelit’ bicara, atau peserta yang kesulitan
menyampaikan gagasannya secara lengkap, triks ”drawing people out” diperlukan.
Triksi ini dimaksudkan untuk meminta pembicara menjelaskan lagi pernyataannya
dan atau mengklarifikasi, serta merumuskan kembali gagasan pokoknya. Triks
”mirroring” serupa tapi tidak sama dengan paraphrasing, karena menyampaikan
kembali pembicaraan peserta tetapi dengan mengutip kembali kalimatnya secara
lengkap. Jadi, fasilitator tidak menggunakan kalimatnya sendiri melainkan kalimat si
peserta (si pembicara) seperti apa adanya.
Trik - Trik Mendengarkan
Berikut adalah 11 macam teknik mendengarkan yang sebaiknya dimiliki fasilitator:
Triks 1: Membahasakan Kembali (Paraphrasing)
Membahasakan kembali merupakan teknik yang paling penting untuk dipelajari.
Teknik ini merupakan dasar dari teknik lainnya.
Teknik ini bersifat menenangkan, membuat peserta paham bahwa ucapannya
dimengerti orang lain.
Terutama digunakan untuk menanggapi jawaban yang berbelit dan membingungkan.
Bagaimana Caranya?
Gunakan kalimat sendiri untuk membahasakan kembali jawaban warga.
Kalau jawabannya pendek, bahasakan kembali secara pendek pula, jika panjang,
bahasakan kembali dengan meringkasnya.
Awali dengan kalimat seperti, ”Tadi ibu mengatakan....................... ”
Sesudahnya perhatikan reaksi orang itu. Sertai dengan kata, misalnya: ”Apa itu
yang ibu maksud?”
Trik 2: Menarik Keluar (Drawing People Out)
Karena jawaban warga kurang lengkap, fasilitator perlu menarik keluar gagasan
yang belum dikatakan.
Gunakan teknik ini bila warga mengalami kesulitan menjelaskan gagasan.
Bagaimana Caranya?
Dahului dengan teknik membahasakan kembali, ”tadi Bapak mengatakan .........”
Lanjutkan dengan pertanyaan terbuka, seperti, ”bisa lebih diperjelas?.”
Ada juga cara lain. Setelah peserta selesai bicara sambut dengan kata sambung
seperti, ”karena” atau ”jadi”.
Trik 3: Memantulkan (Mirroring)
Fasilitator berfungsi sebagai dinding, yang memantulkan kata-kata warga.
Tujuannya, meyakinkan warga bahwa fasilitator mendengarkan ucapannya.
Biasanya digunakan mempercepat diskusi yang lamban. Sesuai untuk
memfasilitasi proses curah pendapat.
Bagaimana Caranya?
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 92
Kalau warga mengatakan satu kalimat, pantulkan kata demi kata setepat-tepatnya.
Tidak kurang tidak lebih. Jika lebih dari satu kalimat, pantulkan kata-kata yang
penting.
Gunakan kata-kata warga, bukan kata-kata fasilitator.
Kalau dia berkata-kata dengan menggebu-gebu, pantulkan dengan nada bicara
tenang.
Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan peserta.
Trik- 4: Mengumpulkan Gagasan (Gathering Ideas)
Adalah teknik mendata gagasan secara cepat. Hanya untuk mengumpulkan dan
bukan hendak mendiskusikannya.
Kumpulkan gagasan dengan memadukan teknik membahasakan kembali. Agar lebih
cepat, gunakan teknik memantulkan. Dengan memantulkan ucapan, warga
merasa didengarkan dan mereka akan ikut menyampaikan gagasan secara singkat.
Biasanya dalam 3 sampai 5 kata. Jadi, kita lebih mudah menuliskannya di papan
tulis.
Bagaimana Caranya?
Awali dengan penjelasan tugas secara singkat. Lakukan curah pendapat.
Kumpulkan gagasan sebanyak-banyaknya.
Tuliskan gagsaan para peserta, apapun yang mereka katakan, dengan memakai
teknik memantulkan atau teknik membahasakan kembali.
Jika peserta telah merasa cukup, sudahi proses ini. Berikan penghargaan terhadap
semua pandangan peserta
Triks- 5: Mengurutkan (stacking)
Adalah semacam teknik menyusun antrian bicara, ketika beberapa orang
bermaksud berbicara pada waktu bersamaan.
Dengan teknik ini, setiap orang akan mendengarkan tanpa gangguan dari orang
yang berebut kesempatan bicara.
Karena setiap orang tahu gilirannya, tugas fasilitator menjadi lebih ringan.
Bagaimana Caranya?
Fasilitator meminta mereka yang hendak bicara untuk mengacungkan tangan.
Fasilitator mengurutkan giliran yang akan bicara.
Fasilitator mempersilahkan peserta untuk bicara ketika tiba gilirannya.
Sesudah peserta terakhir selesai bicara, fasilitator memeriksa jika ada peserta lain
yang hendak bicara. Jika ada, fasilitator kembali melakukan teknik mengurutkan.
Triks-6: Mengembalikan ke Jalurnya (Tracking)
Bayangkan bila ada lima orang yang ingin membicarakan berbagai akibat dari
penumpukan sampah. Empat orang ingin menghitung biaya pengadaan kereta
pengangkut sampah. Tiga orang tertarik membahas pemanfaatan sampah menjadi
pupuk organik.
Biasanya orang menganggap bahwa apa yang ia anggap penting seharusnya terpilih
menjadi topik diskusi. Pada keadaan ini, fasilitator bertugas mengembalikan diskusi
ke jalurnya
Teknik ini akan menenangkan orang yang bingung karena gagasannya tidak
mendapatkan sambutan dari orang lain.
Biasanya teknik ini membuat orang lebih memahami situasi diskusi. Jika ada yang
mencoba menjelaskan bahwa saran dia penting, tunjukkan perhatian. Namun,
jangan bersikap pilih kasih. Tanyakan juga pendapat orang yang lain.
Triks-7: Menguatkan (Encouraging)
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 93
Adalah teknik mengajak orang ikut terlibat dalam diskusi, tanpa membuat mereka
tersiksa karena terpaksa menjadi pusat perhatian.
Dalam diskusi biasanya ada peserta yang hanya duduk dan diam. Diam bukan
berarti malas atau tidak mau tahu. Mereka merasa kurang terlibat. Dengan sedikit
dorongan, temukan sesuatu yang menarik perhatian mereka.
Teknik menguatkan terutama membantu selama tahap awal diskusi, pada saat para
peserta masih menyesuaikan diri. Bagi peserta yang lebih terlibat, mereka tidak
membutuhkan begitu banyak penguatan untuk berpartisipasi.
Bagaimana caranya?
”Siapa lagi yang ingin menyumbangkan gagasan?”,
”Sudah ada beberapa pendapat dari perempuan, sekarang mari kita dengar
pendapat dari laki-laki”.
”Kita sudah mendengar pendapat ibu Tini tentang prinsip-prinsip umum memilih
kepala desa. Adakah yang ingin memberikan contoh tentang pelaksanaan prinsip
tersebut?”.
”Apakah masalah ini dirasakan oleh semua yang hadir di sini?”.
”Mari kita dengar pendapat dari teman-teman yang sementara ini belum berbicara”.
Triks 8: Menyeimbangkan (Balancing)
Pendapat paling kuat dalam suatu diskusi seringkali datang dari orang yang
mengusulkan topik diskusi. Mungkin ada sebagian peserta yang mempunyai
pendapat lain, tapi belum mau bicara.
Teknik menyeimbangkan membantah anggapan umum bahwa ”diam berarti
setuju”.Teknik menyeimbangkan gunanya untuk membantu orang yang tidak
bicara karena merasa pendapatnya pasti tidak disetujui banyak orang.
Dengan teknik menyeimbangkan, fasilitator sebenarnya menunjukkan bahwa dalam
diskusi orang boleh menyatakan pendapat apapun.
Bagaimana Caranya?
”Baiklah, sekarang kita mengetahui pendirian dari tiga orang. Adakah yang lain atau
memiliki pendirian yang berbeda”?
”Ada yang mempunyai pendangan lain?”
”Apakah klita semua setuju dengan ini?”.
Triks 9: Membuka Ruang (Making Space)
Teknik membuka ruang adalah teknik membuka kesempatan kepada peserta yang
pendiam untuk terlibat dalam diskusi.
Dalam setiap diskusi selalu ada yang bicara terus, ada yang jarang bicara. Pada saat
diskusi berlangsung cepat, orang pendiam dan yang berpikir lambat mungkin
mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri.
Ada orang yang tidak mau berperan banyak, karena tidak ingin dianggap ingin
menang sendiri. Ada pula yang ikut dalam diskusi sambil meraba-raba apakah ia
dapat diterima atau tidak. Banyak juga yang enggan bicara karena menganggap
dirinya bodoh. Maka, fasilitator perlu membuka ruang partisipasi.
Bagaimana Caranya?
Amati peserta diskusi yang pendiam. Perhatikan gerak tubuh atau mimik mukanya,
apakah menunjukkan bahwa mereka ada hasrat untuk bicara?
Persilakan mereka untuk bicara.”Apakah ada yang hendak Ibu kemukakan?”.
”Apakah Bapak ingin menambahkan sesuatu?” ”Kelihatannya Anda mau mengatakan
sesuatu?”
Jika mereka mundur, perlakukan mereka dengan ramah dan segeralah beralih.
Tak seorangpun suka dipermainkan. Setiap orang berhak memilih kapan ia
berpartisipasi.
Jika si pendiam tampaknya ingin bicara, jika perlu tahan orang lain, untuk bicara.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 94
Triks - 10: Diam Sejenak (Intentional Silence)
Adalah berhenti bicara selama beberapa detik. Menunggu sejenak agar si
pembicara menemukan apa yang ingin ia katakan.
Banyak orang membutuhkan keadaan tenang untuk untuk mengenali pemikiran
atau perasaannya. Kadang - kadang berhenti bicara beberapa detik sebelum
mengatakan sesuatu yang mungkin berisiko. Ada pula yang diam sejenak untuk
menyusun pikirannya.
Gunakan teknik ini jika peserta diskusi terlalu mudah berbicara. Teknik ini akan
mengajak mereka untuk berpikir lebih mendalam.
Bagaimana Caranya?
Hening selama lima detik tampaknya begitu lama, Banyak orang tak sabar
dengan ”keheningan” tersebut. Jika fasilitator mampu melakukannya, orang lain pun
akan mampu.
Tetaplah tenang. Pelihara kontak mata pada pembicara.
Jangan berkata apapun. Bahkan tidak juga berdehem atau batuk-batuk kecil atau
menggaruk dan menggeleng-gelengkan kepala. Tetaplah tenang dan berikan
perhatian.
Jika perlu, angkat tangan untuk memberi isyarat kepada orang-orang agar tidak
memecahkan keheningan.
Triks-11: Menemukan Kesamaan Pemikiran Dasar
Teknik menemukan kesamaan pemikiran dasar terutama berguna ketika peserta
diskusi terbelah oleh perbedaan pendapat. Teknik ini dapat memperjelas letak
persamaan dan pertentangan pendapat yang terjadi dalam diskusi.
Teknik ini dapat membangkitkan harapan. Membuat warga tersadar bahwa mereka
saling bertentangan, mereka memiliki kesamaan tujuan. Untuk hal yang dasar
mereka memiliki banyak kesamaan.
Bagaimana Caranya?
Katakan bahwa kita akan merangkum hal-hal yang menjadi perbedaan dan
persamaan di dalam kelompok diskusi.
Ringkaskan perbedaan-perbedaan.
Catat aspek-aspek dasar yang sama.
Periksa catatan tersebut bersama peserta.
2. Teknik Bertanya
Agar proses fasilitasi berhasil, fasilitator harus mempersiapkan segala sesuatunya
dengan matang. Sebagai acuan dalam diskusi penting dilakukan untuk membuat daftar
pertanyaan kunci supaya proses diskusi tidak melebar kemana-mana. Dalam
pelaksanaan juga perlu diperhatikan karakteristik peserta supaya kita dapat mengatasi
peserta-peserta yang ‘sulit’ (dominan, diam saja, ngobrol sendiri dan sebagainya).
Anggapan banyak pihak, keterampilan yang paling dibutuhkan untuk memfasilitasi
adalah “pandai berbicara” padahal keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh
seorang fasilitator adalah mendengarkan dan bertanya. Bertanya adalah keterampilan
yang mutlak harus dikuasai oleh fasilitator, karena hakekat dari fasilitasi dan komunikasi
partisipatif adalah menggali dengan pertanyaan-pengalaman peserta dan membantu
proses agar peserta bisa menganalisa sendiri masalah-masalah yang dihadapi dan
menemukan jalan pemecahannya. Tidak jarang ditemui, biasanya terjadi pada fasilitator
pemula, fasilitator panik dan bukannya menggali pemahaman peserta akan tetapi malah
menyimpulkan dan berceramah berdasarkan pengetahuannya dengan
mengatasnamakan pengalaman belajar para peserta. Di lain pihak fasilitator juga
seiringkali tidak sabar untuk “menunggu” peserta berpikir dan mendengarkan peserta
dalam mengungkapkan isi pikirannya.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 95
Agar peserta bisa mengungkapkan isi pikirannya, dan fasilitator konsentrasi
mendengarkan yang diungkapkan peserta maka kita perlu dibantu oleh beberapa
pertanyaan. Pertanyaan itu akan membuat peserta lain dan kita lebih mengerti makna
yang ingin diungkapkan oleh si pembicara.
Teknik bertanya dalam proses fasilitasi sebenarnya sederhana, yang paling penting
harus tetap mencerminkan komunikasi yang dialogis dan multi arah sehingga proses
diskusi bukan hanya milik fasilitator akan tetapi milik para peserta diskusi. Artinya
fasilitator harus memberikan ruang kepada peserta untuk mengungkapkan pendapat
dan pengalamannya.
Secara teknis sebaiknya diperhatikan agar:
1) Setiap pertanyaan yang diajukan tidak panjang lebar–singkat dan jelas, jika perlu
ulangi sampai peserta merasa jelas, terutama jika pertanyaan tersebut hanya
ditujukan pada peserta tertentu.
2) Usahakan jangan sampai peserta “gelagapan” atau malah gugup menjawabnya,
maka hindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tendensius apalagi dengan
gaya bertanya yang menghakimi.
3) Tidak terjadi debat kusir apabila ada pertanyaan dari peserta dilempar kepada
peserta lainnya.
Contoh jenis-jenis pertanyaan yang paling sering digunakan:
Pertanyaan Ingatan
Dimana Anda mengalami?
Kapan hal itu terjadi?
Apakah kejadian seperti itu pernah terjadi pada diri Anda?
Dengan pengalaman ini, apakah bisa dikatikan dengan pengalaman Anda
sebelumnya?
Pertanyaan Pengamatan
Apa yang sedang terjadi?
Apakah Anda melihatnya?
Pertanyaan Analitis
Mengapa perbedaan itu terjadi?
Bagaimana akibat kegiatan ini terhadap perilaku kelompok?
Pertanyaan Hipotetik (Memancing Praduga)
Apa yang akan terjadi jika….?
Kemungkinan apa akibat seandainya….?
Pertanyaan Pembanding
Siapakah yang dalam hal ini yang benar?
Mana yang Anda anggap paling tepat antara…. dan ….?
Pertanyaan Proyektif (Mengungkap ke Depan)
Coba bayangkan seandainya Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan
Anda lakukan?
Apapun bentuk dan jenis pertanyaannya, semuanya mengacu pada pertanyaan
pokok, APA, SIAPA, DIMANA, MENGAPA, KAPAN dan BAGAIMANA. Bila dihubungkan
dengan tahapan dalam alur belajar pengalaman berstruktur, maka kunci–kunci
pertanyaan yang biasa dipakai adalah:
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 96
Mengungkapkan;
1) Mengungkapkan fakta biasanya memakai kata tanya: APA, SIAPA, DIMANA dan
KAPAN ;
2) Mengungkapkan fakta atau pendapat (opini) bisanya memakai kata kunci
BAGAIMANA ;
3) Mengungkapkan apa yang nyata-nyata terjadi dan dialami peserta memakai kata
kunci APA, SIAPA, DIMANA dan KAPAN selain itu juga jenis-jenis ’pertanyaan
ingatan’ dan ’pengamatan’ banyak digunakan dalam tahap ini.
Menganalisa dan kesimpulan menggunakan kata kunci BAGAIMANA dan MENGAPA.
Jenis pertanyaan ’analitik’, hipotetik’ dan ’pembanding’ juga lebih banyak digunakan.
Jenis pertanyaan ’proyektif lebih tepat digunakan pada tahap kesimpulan.
Bagaimana pertanyaan-pertanyaan fasilitator dapat membantu masyarakat
menganalisis masalah mereka sendiri.
Kalau sebagai fasilitator/pemicu kita tidak boleh memberikan jawaban kita sendiri
terhadap masalah masyarakat, bagaimana kita bisa membantu mereka? Sebagai satu
titik awal, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan untuk merinci lebih jauh
masalah yang sedang dibahas dan secara perlahan mendorong kelompok untuk
menganalisis masalah itu.
Kombinasi pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti yang digambarkan dalam model
tehnik bertanya di bawah ini bisa membantu kita. Pastikan bahwa ketika bertanya, Anda
tidak memasukkan gagasan Anda sendiri dalam pertanyaan itu. Misalnya, “Apakah
anda pernah mencoba ………?” atau ”Menurut saya, menggunakan pupuk itu cara
terbaik. Bagaimana menurut Anda ?”.
Nilai/idiologi MENGAPA
Pendapat
APA BAGAIMANA
Fakta
SIAPA DIMANA KAPAN
Gambar 18. Teknik Bertanya
Enam (6) pertanyaan pembantu: Siapa, Kapan, Dimana, Apa, Bagaimana, Mengapa –
dapat juga dilihat dengan cara lain sebagaimana digambarkan pada model di atas.
Pertanyaan pembantu dapat membantu Anda mencari berbagai jenis informasi dan
mendorong terciptanya pemahaman bersama antar anggota kelompok dengan cara
yang berbeda-beda. Pertanyaan “Mengapa” merupakan pertanyaan paling intens
karena menggali apa yang menjadi nilai atau keyakinan kita dan jawabannya bisa jadi
sangat personal sifatnya. Meskipun sangat penting bagi anggota kelompok untuk
memahami nilai-nilai dan keyakinan sesama anggotanya, kadang-kadang pertanyaan
“mengapa” bisa dipandang sebagai agresif atau depensif. Sebagai seorang fasilitator,
Anda harus sadar tentang kapan menggunakan pertanyaan “mengapa”. Anda masih
bisa mendorong terjadinya sharing nilai atau keyakinan dengan menggunakan model
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 97
segitiga untuk bertanya. Misalnya, daripada langsung bertanya, “mengapa” Anda bisa
bertanya, “Apa yang mendorong Anda untuk berpendapat seperti itu? Atau “Bagaimana
Anda sampai pada kesimpulan itu?”
Tabel 5. Kiat Menciptakan Pertanyaan yang Indah
Latar Belakang Identifikasi Masalah
Apa yang sudah Anda persiapkan untuk ……? Apa yang Anda lihat sebagai masalah?
Apa yang sudah pernah Anda coba selama Apa yang Anda lihat sebagai hambatan
ini? utama?
Bisakah Anda ingat bagaimana hal itu terjadi? Apa paling membuat Anda khwatir
Apa yang membuat Anda melakukan semua terhadap……?
ini? Apa yang Anda pertimbangkan sebagai
kesulitan utama?
Mencari Contoh Penggambaran (Deskripsi)
Bisa Anda memberikan sebuah contoh? Seperti apa, coba gambarkan?
Apa contohnya? Ceritakan saya tentang hal itu?
Seperti apa, semisal? Apa yang terjadi?
Bisakah Anda memberikan gambarannya? Bisa Anda ceritakan dengan bahasa
Anda sendiri?
Penilaian Klarifikasi (Meminta Kejelasan)
Bagaimana perasaan Anda tentang hal ini? Bagaimana pendapat Anda jika hal ini
Bagaiman Anda menilai hal itu? Anda anggap tidak masuk akal?
Apa yang membuat hal ini seperti ini? Apa yang membuat Anda bingung, bisa
Apa yang menurut Anda terbaiuk dari hal itu? dijelaskan?
Bisakah Anda jelaskan Apa yang Anda
maksud dengan………?, Apa
maksudnya?
Alternatif Explorasi (Penggalian)
Apa ada kemungkinan lain? Bagaimana jika Anda menjelaskan lebih
Jika Anda memiliki pilihan Apa yang akan lanjut hal itu?
Anda lakukan? Apa ada sisi pandang lain untuk
Apa jawaban yang paling mungkin? menjelaskan hal itu?
Apa yang akan terjadi jika Anda lakukan dan Apa reaksi Anda terhadap hal ini?
Anda tidak lakukan hal itu?
Pendalaman Perencanaan
Bisa Anda ceritakan lebih lanjut?, Apalagi? Bagaimana Anda memperbaiki situasi
Adakah hal lain yang ingin Anda tambahkan? ini?
Apa yang bisa Anda lakukan dalam kasus Apa yang Anda rencanakan untuk
seperti ini? mengatasi hal itu?
Gagasan apa lagi yang Anda miliki? Apa yang Anda lakukan dalam kasus
yang seperti itu?
Apa rencana yang Anda butuhkan untuk
melakukan hal itu?
Prediksi dan Hasil Alasan
Apa yang Anda pikirkan akan bisa berhasil? Apa alasan Anda memilih langkah ini?
Apa yang pasti memiliki dampak besar? Bagaimana Anda menjelaskan hal ini?
Apa yang terjadi jika hal ini dilakukan atau hal Mengapa Anda begitu yakin dengan
ini tidak dilakukan? kegiatan ini?
Apa alur pikir dari kegiatan ini?
Kegagalan Relasi
Apa yang akan terjadi jika hal ini tidak berhasil? Bagaimana hal ini cocok dengan
Apa yang akan terjadi jika hal ini tidak perencanaan Anda?
bekerja? Bagaimana hal ini berpengaruh pada
Bagaimana hal ini bisa berbeda dengan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 98
gagasan awal? kerjaan Anda?
Apa ada rencana baru? Bagimana hubungan antara dua
perencanaan yang berbeda?
Evaluasi
Apakah hal ini baik, buruk atau sedang-
sedang saja?
Sesuai dengan ukuran Anda, apakah kegiatan
berhasil?
3. Teknik Menghadapi Situasi Sulit
Cek perasaan semua peserta/seluruh kelompok: lemparkan pertanyaan kepada
seluruh kelompok untuk memperoleh pendapat kelompok tentang masalah yang
muncul: “Bagaimana menurut yang lain?”
Pusatkan kembali perhatian “Ok Lin, saya rasa itu masalah yang berbeda dengan
apa yang sedang kita bahas–boleh disimpan dulu untuk kemudian kita diskusikan?
Gunakan bahasa tubuh. Berdirilah dan berjalan menuju tengah-tengah ruangan,
ajak peserta untuk terlibat dengan kontak mata dan mencondongkan badan ke
depan.
Gunakan humor yang sepantasnya; kalau digunakan dengan pantas, humor akan
mengurangi ketegangan. Tetapi, kalau bercanda jangan membuat orang lain
ditertawakan.
Ingatkan akan norma kelompok, ”Satu hal yang kita sepakati pada awal pertemuan
adalah jangan ada diskusi swasta. Bisakah kita mentaati norma ini?”
Alihkan perhatian, “Bisa minta waktu 2 menit lagi sebelum kita lanjutkan ke
kesimpulan?”
Jangan mengabaikan atau menghindar. Memang sulit untuk menghadapi resistensi
ketika kita mendeteksinya. Tetapi, mengabaikan atau menghindar dari resistensi
yang ada akan mengacaukan proses-proses selanjutnya. Bukan tidak mungkin akan
menghentikan (membubarkan) proses itu sama sekali.
Tips Menyeimbangkan Dinamika & Mengelola Anggota Kelompok yang Sulit
Menyeimbangkan dinamika kelompok memerlukan kombinasi yang efektif dari berbagai
ketrampilan fasilitasi seperti; mengamati, menyimak, mendiagnosis, memberikan umpan
balik, membuat model, menyemangati dan mengelola konflik.
Beberapa tips umum antara lain :
Mencoba untuk memahami sebanyak mungkin sifat-sifat dari anggota kelompok.
Memfasilitasi penyusunan norma kelompok dan selalu menjadikannya sebagai
rujukan.
Mencermati sejauh mana tahapan kelompok telah terbangun, dan peranan dari
tim, jika diperlukan mintalah agar kelompok juga mencermati hal yang sama.
Mengembangkan kepekaan dan berbagi tanggung jawab dengan kelompok.
Memberikan umpan balik konstruktif kepada kelompok dan anggota mengenai
prilaku mereka.
Bentuk aturan dari perilaku yang tepat dan seperti yang diharapkan.
Bentuk kelompok kecil dengan sangat berhati-hati.
Minta nasihat dari orang di luar kelompok jika perlu.
Tips untuk mengelola anggota kelompok yang sulit
Berikut ini adalah tipe-tipe anggota kelompok yang perilakunya bisa mengakibatkan
kesulitan dalam kelompok, disertai pilihan tentang bagaimana mengelola mereka.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 99
Tabel 6: Intervensi Menghadapi Situasi Sulit
Tipe Kemungkinan Intervensi
Pendiam atau Hargai peran serta apapun. Di luar kelompok semangati dia.
pemalu Berikan umpan balik secara tersendiri. Beri waktu untuk
mempersiapkan suatu topik, dengan cara memberi tahu
sebelumnya. Luangkan waktu. Berikan waktu. Bersabarlah.
Undang untuk bicara atau uji pemahaman dari waktu ke
waktu. Tempatkan dalam kelompok yang saling membantu.
Kelompok lebih kecil
Marah thdp tugas/ Periksa alasan. Berikan umpan balik sesuaikan dan ingatkan
mengecewakan org atuan kelompok. Beri tanggung jawab dalam kelompok.
Hadapi perilakunya jika terjadi. Dukung/perkuat perilaku lain.
Berikan waktu di luar kelompok
Agresif Cari penyebabnya dan hilangkan jika mungkin. Berikan umpan
balik. Rubah kelompok. Ingatkan kelompok tentang aturan.
Hadapi perilakunya ketika terjadi dan perkuat perilaku lain
ketika terjadi. Bentuk alternatif non-agresif. Diskusikan
akibatnya dengan keseluruhan kelompok
Terlalu dominan Luangkan waktu. Berikan umpan balik. Catat tingkat keikut
sertaan. Tempatkan dengan tipe-tipe lain yang semacam.
Tempatkan dalam kelompok yang sama dengan pelatih. Minta
diam. Undang untuk ikut bertangggung jawab atas peran serta
yang lain. Kembangkan sikap asertif terhadap orang lain
Motivasi rendah Periksa alasannya. Berikan peran dalam memilih tugas.
atau malas Tawarkan pilihan kerja. Perkuat, semangati, dukung
keikutsertaan. Beri tanggung jawab. Tantang jika sesuai.
Tempatkan bersama dengan klpk inti yang memotivasi. Terima
dan bersabarlah. Cari terus keterlibatan.
Pelawak Diskusikan dalam kelompok mengenai kegunaan dan
penyalahgunaan humor. Hadapi pelakunya. Berikan umpan
balik dan beri waktu untuk berubah. Dukung perilaku yang
berbeda dari yang ini.
Penyendiri Selalu menerima. Berikan umpan balik jika sesuai. Berikan
dukungan khusus. Alokasikan peran atau tanggung jawab
khusus. Dukung-ciptakan kesempatan untuk meraih
penghargaan.
4. Dinamika Bertanya
Metode ini kita terapkan untuk melakukan pendalaman materi. Sesuai dengan prinsip,
bahwa orang dewasa adalah orang yang telah memiliki berbagai pengalaman, proses
tanya jawab tidak berarti pertanyaan dari peserta harus kita jawab. Kita bisa
memberikan kesempatan kepada peserta yang bersangkutan untuk menggali
pengalamannya sendiri, atau memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk
memberikan jawaban.
Biasanya metode ini digunakan setelah kita menyampaikan materi (seperti ceramah,
demonstrasi, atau penugasan).
5. Curah Pendapat
Metode curah pendapat (asah otak/brainstorming) adalah suatu cara yang cocok untuk
menghasilkan ide-ide baru. Asah otak memungkinkan warga belajar saling bekerjasama
mengumpulkan ide-ide untuk memecahkan masalah mereka.
Metode ini umumnya kita gunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 100
pemecahan masalah tertentu, atau kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan
munculnya gagasan-gagasan baru.
Ada dua tahap pengorganisasian dan peraturan dari kegiatan curah pendapat atau
asah otak:
Tahap pertama adalah untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide. Ide tersebut bisa
ditulis di atas lembaran kertas dan memperkenalkannya di atas papan atau
menuliskannya secara langsung dalam sebuah bagan-bagan. Warga dilarang
berkomentar selama tahap ini.
Tahap kedua adalah mengevaluasi ide-ide yang dihasilkan selama tahap
pertama. Kemudian, warga belajar diminta mengelompokan ide-ide yang sama, lalu
memberikan tanda pada setiap kelompok dalam sebuah prioritas (ada kelompok ide
dengan prioritas paling penting, kedua terpenting, dan seterusnya).
Langkah Umum Penggunaan Metode
Identifikasi dan tulis masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta di papan tulis
atau lembaran kertas,
Mintalah peserta untuk memikirkan masalah-masalah tersebut selama beberapa
menit,
Mintalah ide-ide/gagasan seketika peserta (tanpa perlu dipikirkan terlebih
dahulu) terhadap pemecahan masalah tersebut,
Mintalah warga belajar untuk memberi tanggapan atau mendebat ide-ide yang
dilontarkan tersebut,
Tunjuklah seseorang untuk menulis ide-ide tersebut di papan tulis,
Hentikan kegiatan brainstorming pada beberapa titik permasalahan dan mintalah
warga belajar untuk menjelaskan setiap ide tersebut,
Kelompokkan ide-ide tersebut, lalu tentukan tingkat prioritasnya, dan
Diskusikan dan garisbawahi ide-ide yang telah disetujui bersama.
VIII. REFERENSI
Kemenkes RI, Buku Sisipan STBM: Kuriklum dan Modul Pelatihan Fasilitator
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan, Jakarta:2013
Modul Teknologi Advokasi Kesehatan Bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli,
Puspromkes Kemenkes, 2011
Materi Teknik Fasilitasi Partisipatif, Eko Dermawan, Juli 2012
(http://kpmbwi.blogspot.co.id/2012/07/materi-teknik-fasilitasi-partisipaitf.html)
WHO, 1989 Health Principles of Housing, Geneva.
Hunter, et all 1993, Relationship Among Attitude, Behavioral Intention and Behavior,
first published.
JHU, 1999, Issue in Health Advocay, Baltimore, Maryland.
Kaner, S,et all 2007, Facilitator’s Guide to Participatory Decision Making, Jossey-
Bass.
Djohani, Rianingsih, Ed. 1996, Buku Acuan Penerapan PRA, Berbuat Bersama
Berperan Setara, Studio Drya Media, KPDTNT, Bandung.
IX. LAMPIRAN (Terlampir)
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 101
MODUL MI.4
PEMICUAN STBM-STUNTING DI KOMUNITAS
I. DESKRIPSI SINGKAT
Modul ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan peserta dalam
menerapkan pendekatan STBM-Stunting ketika memfasilitasi proses pemberdayaan
masyarakat, khususnya untuk memicu masyarakat berubah perilak terkait sanitasi dan
pencegahan stunting di komunitas. Dalam materi ini dibahas bagaimana melakukan
kegiatan pra pemicuan, pemicuan, hingga fasilitasi paska pemicuan STBM-Stunting.
Untuk memastikan peserta mampu melakukan, maka metode utama dalam modul ini
adalah simulasi pemicuan STBM-Stunting yang dilakukan di dalam kelas serta
mempraktikkannya di komunitas.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melaksanakan pemicuan STBM-Stunting
di komunitas.
B. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:
1. Melakukan kegiatan pra pemicuan,
2. Melakuka kegiatan pemicuan,
3. Melakukan kegiatan paska pemicuan.
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai berikut:
A. Pokok Bahasan 1: Pra Pemicuan
1. Observasi PHBS dan penapisan/screening faktor resiko stunting.
2. Persiapan pemicuan dan menciptakan suasana yang kondusif sebelum
pemicuan.
3. Persiapan teknis dan logistic.
B. Pokok Bahasan 2: Pemicuan
1. Pengantar
2. Alat-alat utama untuk pemicuan
3. Elemen pemicuan dan faktor penghambat pemicuan
4. Langkah-langkah pemicuan di komunitas
C. Pokok Bahasan 3: Paska Pemicuan
1. Cara membangun ulang komitmen,
2. Pilihan teknologi sanitasi untuk 8 pilar STBM-stunting,
3. Membangun jejaring layanan penyediaan sanitasi dan gizi,
4. Pendampingan dan monitoring,
5. Menggali media promosi untuk perubahan perilaku yang berkelanjutan.
IV. METODE BAHAN BELAJAR
Ceramah tanya jawab, diskusi kelompok, simulasi, putar film, praktik pengisian lembar
observasi, praktik pengukuran antropometri, dan praktik kerja lapang.
V. MEDIA DAN ALAT BANTU
Bahan tayang (slide ppt, film), LCD, komputer/laptop, flipchart (lembar balik), spidol,
metaplan, lembar diskusi kelompok, tali, kain tempel, alat-alat dan bahan untuk
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 102
pemicuan, panduan simulasi, panduan praktik lapang, buku KIA, lembar observasi,
Tabel WHO 2005, Film singkat pengukuran tinggi badan, Film pemicuan STBM, Alat
LiLA (lingkar lengan atas), panduan praktik pengukuran antropometri, panduan
pengisian lembar observasi, panduan praktik kerja lapang.
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 24 jam pelajaran (T=6 jp,
P=8 jp, PL=10 jp) @45 menit. Untuk mempermudah proses pembelajaran dan
meningkatkan partisipasi seluruh perserta, dilakukan langkah-langkah kegiatan sebagai
berikut:
Langkah 1. Penyiapan Proses Pembelajaran (20 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Menyampaikan salam dan menyapa peserta dengan ramah
b. Memperkenalkan diri
c. Melakukan bina suasana
d. Memberikan tugas penyusunan puzzle “Tahapan Kegiatan Pemicuan” kepada
peserta.
e. Menyampaikan ringkasan pokok bahasan tahap demi tahap, tujuan, waktu dan
metode yang akan digunakan.
2. Kegiatan Peserta
a. Mempersiapkan diri dan alat tulis yang diperlukan
b. Menjawab salam
c. Menyusun puzzle “Tahapan Kegiatan Pemicuan”.
Langkah 2: Penyampaian Pokok Bahasan (1.050 menit)
Pokok Bahasan 1: Pra Pemicuan (270 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Membagi peserta dalam kelompok untuk melakukan praktek pemicuan, masing
masing 5-8 orang disesuaikan jumlah peserta dan titik lokasi pemicuan.
b. Menggali pendapat peserta melalui curah pendapat terkait kegiatan apa saja
yang dilakukan pada tahap pra pemicuan.
c. Mengajak peserta untuk melakukan diskusi kelompok mengidentifikasi data dan
informasi apa saja yang diperlukan sebelum pemicuan yang terkait PHBS dan
stunting menggunakan LP4.1.
d. Menayangkan video pengukuran antropometri dan praktik pengukuran LILA.
e. Memberikan tugas kelompok menggunakan formulir observasi sesuai panduan
Lembar Penugasan LP4.2.
f. Memberi kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang
jelas, dan memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan
peserta.
g. Meminta peserta per-kelompok mempersiapkan diri untuk melakukan observasi
lapangan.
h. Melakukan diskusi kelompok terkait hasil observasi lapangan.
i. Meminta peserta dalam masing-masing kelompok untuk menyusun game bina
suasana untuk proses pemicuan di komunitas, menggunakan Panduan
Penugasan seperti LP.4.3.
j. Mendemonstrasikan penggunaan alat dan elemen pemicu (termasuk sikap dan
penampilan).
k. Membagikan panduan persiapan praktek lapangan dan simulasi kelompok yaitu
LP4.4.
l. Mengajak peserta mensimulasikan pemicuan per masing masing kelompok
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 103
pemicu.
m. Membagikan panduan pemicuan masyarakat yaitu LP4.5 serta lampirannya.
n. Meminta peserta per kelompok untuk mempersiapkan diri untuk praktek memicu
esok harinya, meliputi skenario pemicuan berdasarkan hasil observasi.
sebelumnya, pertanyaan pemicu, alat dan perlengkapan dan pembagian peran.
2. Kegiatan Peserta
a. Menyimak materi yang disampaikan oleh fasilitator
b. Mencatat hal-hal penting dari materi yang disampaikan, maupun hal-hal yang
belum jelas untuk ditanyakan atau meminta penjelasan ulang.
c. Menyampaikan pendapat dari pertanyaan fasilitator
d. Mengajukan pertanyaan kepada fasilitator bila ada yang belum jelas.
e. Melakukan observasi lapangan
f. Melakukan simulasi/latihan dan persiapan pemicuan.
Pokok Bahasan 2: Pemicuan (690 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Menayangkan Video Pemicuan.
b. Meminta peserta dalam masing masing kelompok mengidentifikasi langkah dan
kegiatan serta elemen pemicu apa saja yang ditayangkan dalam video.
c. Memberikan penjelasan tentang pembagian peran dan persiapan Tim Pemicu
termasuk persiapan teknis dan logistik.
d. Melakukan pemicuan di masyarakat.
e. Setelah kembali dari lapangan, fasilitator memfasilitasi peserta mereview
pengalaman melakukan praktik pemicuan.
2. Kegiatan Peserta
a. Menyimak materi yang disampaikan oleh fasilitator
b. Melakukan penugasan-penugasan sesuai panduan fasilitator
c. Mencatat hal-hal penting dari materi yang disampaikan, maupun hal-hal yang
belum jelas untuk ditanyakan atau meminta penjelasan ulang.
d. Melakukan simulasi/latihan dan persiapan pemicuan.
Pokok Bahasan 3: Paska Pemicuan (90 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Menggali pendapat peserta latih melalui curah pendapat terkait kegiatan apa
saja yang relevan dilakukan pada tahap pasca pemicuan.
b. Mengajak peserta untuk merangkaikan kembali hubungan langkah langkah
kegiatan sejak pra pemicuan, pemicuan dan pasca pemicuan untuk sebuah
upaya perubahan perilaku.
3. Kegiatan Peserta
a. Menyimak materi yang disampaikan oleh fasilitator
b. Mencatat hal-hal penting dari materi yang disampaikan, maupun hal-hal yang
belum jelas untuk ditanyakan atau meminta penjelasan ulang.
Langkah 3. Kesimpulan (10 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Merangkum sesi pembelajaran dengan menegaskan poin-poin penting
b. Memfasilitasi pemberian jawaban,baik dari fasilitator maupun dari peserta
lain.Memberikan komentar, penilaian, saran dan kritik pada lembar penilaian
c. Meminta komentar, penilaian, saran bahkan kritik dari peserta pada kertas
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 104
evaluasi yang telah disediakan.
d. Fasilitator menutup sesi pembelajaran dengan memastikan tercapainya TPU dan
TPK sesi.
e. Fasilitator menutup pertemuan dengan salam
2. Kegiatan Peserta
a. Mencatat hal-hal yang penting
b. Menanyakan hal-hal yang kurang jelas
c. Membalas salam
VII. URAIAN MATERI
Pengantar
Pemicuan STBM-Stunting adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku tentang
deteksi faktor resiko stunting yang dimiliki individu untuk dirubah menjadi faktor resiko
negatif atas kesadaran dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan
individu atau masyarakat.
Maksud pemicuan STBM-Stunting adalah masyarakat secara bersama-sama bisa
menyadari kondisinya dari tidak melakukan pencegahan stunting karena beberapa
alasan setelah terpicu dengan cepat mengambil keputusan secara kolektif mau
melakukan pencegahan stunting bayi dan anak. Tujuan pemicuan STBM-Stunting
adalah merubah kebiasaan dan perilaku yang mengakibatkan baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap kejadian stunting menjadi melakukan pencegahan
stunting bayi dan anak melalui di tingkat individu (ibu/bumil), melakukan PMT untuk
mencegah KEK, Bumil KEK beresiko BBLR, BBLR beresiko stunting. Melakukan minum
tablet tambah darah selama kehamilan, menjaga sakit selama kehamilan, menyediakan
akses air bersih dan sanitasi yang sehat, memberi IMD sewaktu bayi dilahirkan,
memberi ASI eksklusif, memberi vit A, memberi immunisasi lengkap, dan MPASI. Di
tingkat kelompok masyarakat terbentuk panitia penyelenggara penyediaan PMT dan
MPASI lokal non subsidi pemerintah untuk 1000 hari pertama kehidupan anak dan
penimbangan berat badan anak untuk pemantauan pertumbuhan anak.
POKOK BAHASAN 1: KEGIATAN PRA PEMICUAN
A. Observasi PHBS dan screening faktor resiko stunting
a. Informasi yang dicari untuk PHBS:
Jumlah KK / kependudukan dibedakan atas kaya, sedang, miskin.
Kondisi geografis
Kepemilikan jamban: cemplung terbuka, cemplung tertutup, leher angsa.
Ada tidaknya aliran sungai, kolam, rawa.
Tradisi/budaya: karakter, tokoh masyarakat.
Sarana dan prasarana umum yang ada di masyarakat seperti sekolah,
madrasah, masjid, gereja, dll.
Ada tidaknya program sanitasi 3 tahun terakhir (proyek/pemberian subsidi
jamban).
b. Informasi yang dicari pada peserta yang hadir di pemicuan untuk screening faktor
resiko stunting:
1. Apakah TB anak < - 2 SD sesuai grafik TB anak menurut umur.
2. Apakah berat badan bayi baru lahir < 2500 gram.
3. Apakah panjang badan baru lahir < 48 cm.
4. Apakah lingkar lengan atas ibu < 23, 5 cm.
5. Apakah gagal memberikan ASI Eksklusif.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 105
6. Apakah gagal memberikan IMD.
7. Apakah gagal melakukan CTPS yang benar (7 langkah).
8. Apakah gagal memberikan immunisasi lengkap.
9. Apakah gagal memberikan Vit A.
10. Apakah gagal minum tablet tambah darah.
11. Apakah pernah dinyatakan Hb darah < 11 Mg/ L.
12. Apakah timbangan BB anak tidak naik/ turun/ berlebihan.
13. Apakah pernah anak sakit berulang batuk/diare/demam.
14. Apakah MPASI tidak mudah ditelan dan disukai anak (buatan
lokal/pabrikan). Jika lokal apakah MPASI itu: bubur sumsum, kacang hijau,
pisang lumat halus, nasi tim saos, papaya.
Jika jawaban Ya, atas pertanyaan yang diajukan, menunjukan jumlah faktor resiko
stunting yang dimiliki peserta pemicuan tersebut. Skor faktor resiko stunting
tertinggi: 14 dan terendah 0. Peserta pemicuan dengan skor 0 menjadi sumber
belajar ketika pemicuan.
B. Persiapan Pemicuan dan Menciptakan Suasana yang Kondusif Sebelum
Pemicuan
Persiapan pemicuan dan menciptakan suasana yang kondusif sebelum pemicuan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pemicuan. Persiapan ini dilakukan
dengan kunjungan kepada pemerintah setempat yang akan digunakan sebagai lokasi
pemicuan dan dijelaskan secara rinci kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses
pemicuan STBM-Stunting termasuk proses pemberdayaan masyarakat yang akan
dilaksanakan di lapangan dan memastikan bahwa pemerintah setempat dan tokoh
masyarakat menerima konsep dan prinsip tanpa subsidi, sehingga perlu dibangun
komitmen bahwa kehadian tim tidak akan membawa bantuan.
Hal yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah setempat lokasi pemicuan adalah:
• Penting dan perlunya kegiatan pemicuan STBM-Stunting ini dilakukan berdasarkan
hasil data dan fakta observasi PHBS yang dilakukan sebelumnya.
• Pemilihan prioritas lokasi pemicuan berdasarkan data dan masukan dari pemerintah
setempat. Non subsidi dari tokoh-tokoh utama yang ada di masyarakat, misalkan
tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.
• Penyusunan rencana jadwal dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Komponen yang perlu diketahui oleh pemerintah dan tokoh setempat antara lain:
• Tanggal kunjungan lapangan untuk pemicuan dan peserta.
• Kegiatan di lapangan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan
untuk perubahan perilaku secara kolektif, keluaran yang diharapkan setelah
pemicuan, hasil pemicuan yang akan diserahkan kepada pemerintah setempat untuk
ditindaklanjuti.
• Peran dan tanggungjawab pemerintah setempat.
• Dukungan dan komitmen dalam menerapkan prinsip
• Waktu kegiatan dan tindaklanjutnya.
• Logistik yang disediakan.
C. Persiapan Teknis dan Logistik
Sebelum melakukan kegiatan pemicuan STBM-Stunting di komunitas/masyarakat, tim
perlu menyiapkan beberapa peralatan dan logistik yang akan digunakan untuk
mendukung proses pemicuan. Persiapan teknis dan logistik ini menjadi bagian penting
yang akan mendukung proses analisa partisipatif yang membantu masyarakat untuk
mengenal kondisi wilayahnya beserta dengan permasalahan dan potensi yang ada
sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat untuk menemukan solusi secara
kolektif dari mereka sendiri.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 106
Persiapan teknis dan logistik ini rinciannya tergantung dari lokasi dan rencana proses
pemicuan yang dilakukan oleh tim pemicu sehingga tidak ada standar baku yang harus
disiapkan. Misalnya bagaimana teknis pemberangkatan tim pemicu, teknis masuk
sebelum pemicuannya dan proses pemicuannya. Bisa jadi proses pemicuan dilakukan
pada saat ada kegiatan posyandu, PKK, temu warga dll.
Sebelum melakukan pemicuan, tim pemicu perlu mempersiapkan alat-alat yang
dibutuhkan, seperti tepung, dedak, botol air mineral, puzzle simulasi diagram F STBM-
Stunting, sabun, ember, kertas metaplan, spidol, kertas potong, lem,dll.
Peserta perlu mendiskusikan lebih detail dengan anggota kelompok mengenai alat
yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan rencana proses melakukan pemicuan di
masyarakat, alat untuk screening buku KIA tahun 2016, alur kontaminasi diagram F
STBM-Stunting, dan diagram pilar faktor resiko stunting.
POKOK BAHASAN 2: PEMICUAN
A. Pengantar
Dalam pemicuan di masyarakat, tidak ada langkah-langkah yang baku, namun
pemetaan sosial mesti dilakukan pertama sekali. Lokasi pemetaan sosial sebaiknya
dilakukan di lahan (halaman) terbuka. Hasilnya kemudian harus dipindahkan ke kertas
plano.
Pemicuan bisa dilakukan di ruang terbuka maupun tertutup, asal bisa membangkitkan
elemen pemicuan seperti rasa jijik, takut penyakit, berdosa, takut anak tidak akan
sukses, takut miskin, dll., yang bisa memicu masyarakat untuk berubah atas
kesadarannya. Beberapa kegiatan bisa dilakukan pada proses pemicuan. Untuk
pemicuan pilar 1 STBM-Stunting, Stop Buang Air Besar Sembarangan, tim pemicu bisa
mengajak masyarakat melakukan kegiatan mencari tinja, menghitung tinja, dan
demonstrasi air yang terkena tinja. Untuk pilar 2 STBM-Stunting, Cuci Tangan Pakai
Sabun, tim pemicu bisa mengajak masyarakat bermain alur penularan penyakit
(diagram F) dan simulasi cuci tangan pakai sabun. Untuk Pilar 7 STBM-Stunting,
Pemberian Makan Bayi dan Anak, tim pemicu bisa mengajak anak-anak yang biasanya
dibawa ke lokasi pemicuan untuk bermain dan berdiri sejajar berdasarkan umum dan
tinggi badan kemudian ditanyakan pola makan yang mereka terima sejak bayi. Tim
pemicu bisa menyesuaikan kegiatan sesuai dengan tujuan pemicuan yang akan
dilakukan.
B. Alat-Alat utama untuk Pemicuan
Dasar utama pemicuan adalah bagaimana masyarakat memahami alur penularan
penyakit yang disebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat, sehingga masyarakat
menjadi tahu dan sadar dengan sendirinya, terkait perilaku dan kondisi lingkungannya
selama ini. Dengan mengetahui kondisi tersebut, masyarakat diharapkan mempunyai
komitmen secara kolektif untuk berubah perilakunya dan mempunyai kemauan untuk
membangun akses sanitasi secara mandiri dan bersama-sama mencegah stunting.
Dengan diagram F STBM-Stunting, individu dapat menyadari bagaimana mendeteksi
kondisi faktor resiko dirinya dan sesuai kondisi faktor resiko dirinya dapat menentukan
perubahan perilaku apa saja (faktor resiko negatif stunting) yang harus dimiliki untuk
mencegah stunting bayi dan anak. Di tingkat kelompok masyarakat, dibangun sarana
tempat penyediaan PMT dan MPASI non subsidi lengkap dengan sanitasi dapur; yang
dapat mencegah terjadinya cemaran hasil olahannya oleh sumber kontaminan: tangan
penjamak makanan, lalat, debu permukaan lantai alat masak dan makan minum,
limbah cair tempat cucian, feses penjamak carier gastro interitis, bahan makanan yang
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 107
rusak. Di tingkat Puskesmas/pemerintah mencabut subsidi (prinsip STBM-Stunting non
subsidi). Adapun subsidi hanya diberikan untuk pengobatan (kuratif) untuk mengatasi
stunting yang sudah terjadi pada bayi dan anak atau pada ibu hamil yang berada dalam
kondisi kesehatan yang tidak baik sehingga memiliki risiko melahirkan anak stunting
dan sakit.
Alat-alat utama pemicuan digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan partisipasi
dan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menganalisa kondisinya mereka sendiri.
Ada beberapa alat yang digunakan, seperti:
a. Pemetaan, bertujuan untuk mengetahui/melihat peta wilayah BAB masyarakat,
jumlah anggota keluarga, faktor risiko stunting, perilaku ke posyandu, serta sebagai
alat monitoring (paska pemicuan, setelah ada mobilisasi masyarakat).
b. Transect walk/Penelusuran wilayah, bertujuan untuk melihat dan mengetahui
lokasi yang paling sering dijadikan tempat BAB. Dengan mengajak masyarakat
berjalan ke lokasi BAB terbuka/ sembarangan dan berdiskusi di tempat tersebut,
diharapkan masyarakat akan merasa jijik. Lebih jauh, diharapkan orang yang biasa
BAB di tempat tersebut akan terpicu rasa malunya. Berkaitan dengan pencegahan
stunting dapat melihat jenis MPASI/PMT rumah tangga yang dapat memicu untuk
memilih MPASI lokal dan melihat kondisi sanitasi dapur warga masyarakat.
c. Diagram F/Alur Kontaminasi (Oral Fecal) dan Stunting; mengajak masyarakat
untuk melihat bagaimana kotoran manusia dapat dimakan oleh manusia yang
lainnya atau mereka sendiri dan juga menjadi alur penyebab stunting.
Laporan WHO tahun 2009 menyebutkan bahwa sekitar 1,1 juta anak usia di bawah
5 tahun meninggal karena diare. Sementara UNICEF memperkirakan bahwa setiap
30 detik ada satu anak yang meninggal karena diare. Kematian diare pada balita di
negara-negara berkembang mencapai 1,5 juta jiwa. Data di Indonesia menunjukkan
diare adalah pembunuh balita kedua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan
Akut). Di Indonesia setiap tahun 100.000 balita meninggal karena diare. Penyebab
utama diare adalah bakteri Eschericia coli selanjutnya disingkat menjadi E.coli. E.
coli adalah tipe bakteri fecal coliform yang biasanya terdapat pada alat pencernaan
binatang dan manusia. Adanya E.coli di dalam air adalah indikasi kuat adanya
kontaminasi adanya kotoran manusia dan hewan.
Diagram penyebaran kuman diare biasa disebut Diagram F. Diagram ini pertama
ditemukan oleh Wagner dan J.N. Lanoix pada tahun 1958. Diagram F
menggambarkan bagaimana bakteri E.coli yang ada di dalam kotoran manusia dan
hewan bisa masuk ke perut manusia melalui mulut dengan beberapa cara, antara
lain melalui tangan (fingers), air (fluid), dan lalat (flies).
Lalat sering hinggap di kotoran manusia dan hewan. Pada saat hinggap di
makanan, lalat menempelkan kotoran manusia dan hewan ke makanan dan
minuman yang tidak ditutup dengan baik. Makanan dan minuman yang tidak ditutup
rapat, juga bisa terkena udara yang mengandung kuman penyakit dan bisa
menyebabkan diare.
Diare, baik pada ibu hamil maupun balita dapat menyebabkan kurang optimalnya
asupan gizi dan juga sebagai pertanda adanya penyakit kronis lainnya. Kekurangan
asupan gizi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan
stunting. Untuk mencegah stunting, alur kontaminasi penyakit harus diputus
sebagaimana dijelaskan pada Gambar.19 berikut sehingga akan tercipta manusia-
manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 108
Keterangan:
Alur penularan/kejadian
Blocking/Upaya Tindakan
Gambar 19. ALur Penularan Penyakit (Diagram F) dan Stunting
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 109
Kotoran manusia yang berserakan ataupun tidak dibuang ke saluran yang benar, dapat
mencemari air. Jika langsung diminum, air tersebut bisa berbahaya. Sehabis buang air
besar/ buang air kecil, tangan kita juga bisa mengandung kuman penyakit diare, yang
bisa masuk ke tubuh kita jika kita tidak membersihkan tangan. Perilaku buang air besar
sembarangan merupakan perilaku yang dapat membantu penyebaran bakteri E. Coli.
Saat turun hujan, E. Coli dapat terbawa ke sumber-sumber air misalnya ke sungai,
danau, dan air bawah tanah. Jika sumber-sumber air ini tidak diolah dengan baik, maka
E. Coli akan masuk ke dalam makanan dan minuman kita. Kuman penyakit yang
terdapat dalam tinja, tidak sengaja masuk ke dalam mulut dan dapat menyebabkan
diare. Diare pada Ibu hamil dan balita mempengaruhi asupan gizi yang dapat
menyebabkan stunting.
Bagaimana kita bisa mencegah penyakit diare yang dapat menyebabkan stunting?
1. Pembuatan jamban sehat, sehingga lalat tidak dapat menyentuh kotoran manusia.
2. Pengelolaan air minum dengan benar mulai dari sumber sampai siap untuk
diminum.
3. Mengolah makanan dengan benar serta menutup makanan.
4. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir pada waktu-waktu
penting.
5. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan mengkonsumsi makanan bergizi serta
vitamin yang dibutuhkan oleh ibu hamil.
6. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang pada balita dan anak.
7. Melakukan pemantauan pertumbuhan balita dan anak dengan datang ke posyandu
secara rutin.
Beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mencegah stunting, digambarkan
pada tabel-7 berikut.
Tabel 7. Faktor Resiko Stunting dan Upaya Pencegahannya
Faktor Resiko Masalah Stunting Pencegahan Stunting
1. Bumil KEK dan 1. Balita pendek - PMT
atau Anemia - Tablet tambah darah
- ANC
- PHBS
- Gizi seimbang
- Dukungan Keluarga
- Kelas Ibu
- Revitalisasi Posyandu
2. BBLR 2. Balita Sangat Pendek - Memberi IMD-ASI Ekslusif
- Memberi Imunisasi lengkap
- Revitalisasi Posyandu
3. Bayi yang tidak 3. Daya tahan tubuh 1. Relaktasi
mendapatkan rendah menyebabkan 2. Donor ASI
ASI Eksklusif penyakit infeksi 3. Kelas Ibu
berulang 4. Konseling ASI
5. Revitalisasi Posyandu
4. Makanan 4. Kebutuhan gizi tidak Kelas Ibu
pendamping ASI tercukupi maka Konseling PMBA
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 110
yang tidak tepat pertumbuhan tidak Revitalisasi Posyandu
optimal
5. Tidak melakukan 5. 6. Penimbangan BB dan
pemantauan 6. Tidak terdeteksi bila pengukuran PB/TB
Pertumbuhan ada gangguan 7. Revitalisasi Posyandu
pertumbuhan. 8. Kunjungan Keluarga
6. Rendahnya 7. Penyakit Infeksi yang - Rumah Tangga Akses Air Bersih
akses Sanitasi berulang dan Sanitasi layak
dan air bersih
Diagram ini mengajak cara merubah perilaku dari tidak mencegah menjadi
mencegah (Stunting). Menurut Kep.Men.Kes. No. 1995/Menkes/SK/XII/2010,
tentang standar Antropometri penilaian status gizi anak, pengertian pendek dan
sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan
menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan
padanan istilah stunted (pendek) dan severely Stunted (sangat pendek).
Balita pendek (Stunting) dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang
atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada
dibawah normal. Balita pendek adalah balita dengan status gizi yang berdasarkan
panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan standar baku WHO-
MGS (Multicentre Growth Reference Study) tahun 2005, nilai z – scorenya kurang
dari -2 SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai z –scorenya kurang dari -3 SD.
Masalah balita pendek dipengaruhi oleh:
1) Kondisi Ibu / Calon ibu
2) Masa janin
3) Masa bayi / balita
4) Penyakit semasa balita
Menurut WHO, prevalensi balita pendek menjadi masalah kesehatan masyarakat
jika prevalensinya 20% atau lebih. Gizi janin bergantung sepenuhnya kepada ibu,
oleh karena itu kecukupan gizi ibu sangat mempengaruhi janin yang dikandungnya.
Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat
menyebabkan Kurang Energi Kronis (KEK). Wanita hamil berisiko mengalami KEK
jika memiliki Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5 cm. Ibu hamil dengan KEK berisiko
melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang jika tidak segera ditangani
dengan baik akan berisiko mengalami Stunting.
Kondisi lain pada ibu hamil adalah Anemia, terutama anemia defisiensi besi. Hal ini
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun
setelahnya. Ibu hamil dinyatakan anemia jika hemoglobin kurang dari 11 G/dLG/dL.
BBLR, yaitu berat bayi lahir kurang dari 2.500 gram, membawa resiko kematian,
gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak berisiko menjadi pendek jika tidak
ditangani dengan baik.
Pada bayi, ASI sangat berperan dalam perolehan nutrisinya. Konsumsi ASI juga
meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga menurunkan resiko penyakit infeksi.
Sampai usia 6 bulan, bayi di rekomendasikan hanya mengkonsumi ASI ekslusif.
ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilakukan selama 6
bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman
lain kecuali obat, vitamin dan mineral). Setelah 6 bulan, disamping ASI diberi
makanan tambahan.
Pelayanan kesehatan balita akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
balita, baik pelayanan kesehatan ketika sehat maupun saat dalam kondisi sakit.
Pelayanan kesehatan pada bayi minimal 4 kali yaitu, satu kali pada umur 29 hari – 2
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 111
bulan, 1 kali pada umur 3-5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur
9-11 bulan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar
(BCG, DPT/HB1-3, Polio1-4, Campak), pemantauan pertumbuhan, stimulasi diteksi
intervensi demi tumbuh kembang (SD, DTK), pemberian Vitamin A, pada bayi umur
6-11 bulan, penyuluhan pemberian ASI Eksklusif dan makanan pendamping ASI
(MPASI).
Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan kesehatan anak umur 12-59
bulan yang memperoleh pelayanan sesuai standar, meliputi pemantauan
pertumbuhan minimal 8 kali pertahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali
setahun, pemberian Vitamin A 2 kali setahun, cakupan pelayanan kesehatan ini
memperkuat 1000 HPK.
Kondisi sanitasi dan akses air minum dan fasiltias sanitasi yang buruk dapat
meningkatkan kejadian penyakit infeksi yang membuat energi untuk pertumbuhan
beralih kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi. Gizi sulit dicerna oleh tubuh
dan terhambat pertumbuhan.
Rumah tangga memiliki akses sanitasi layak bila sanitasi yang digunakan memenuhi
syarat kesehatan, dilengkapi leher angsa, tangki septik, SPAL sendiri atau bersama.
Pentingnya stunting diatasi karena stunting adalah hasil sebagian besar nutrisi tidak
mewadahi serangan infeksi berulang pada 1000 HPK anak. Stunting memiliki efek
jangka panjang kurang kognitif dan perkembangan fisik, mengganggu komponen
kesehatan. Anak memiliki obesitas dikemudian hari, mengurangi hasil kehadiran
sekolah dan mengurangi pendapatan 22% dari seluruh pendapatan tahunan di
masa dewasa.
Rekomendasi untuk pencegahan stunting melalui peningkatan cakupan kegiatan
pencegahan dengan cara identifikasi pengukuran dan pemberian gizi ibu pada
wanita usia subur, mendukung praktek ASI eksklusif, PMT, mencegah infeksi
berbasis masyarakat.
Upaya intervensi tersebut meliputi:
1) Pada ibu hamil, diberi PMT, dijaga tidak boleh sakit, diberi tablet Fe 90 tablet.
2) Pada saat bayi lahir, inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI Eksklusif.
3) Bayi usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun, selain ASI, MPASI, Vitamin A,
imunisasi lengkap.
4) Pemantauan pertumbuhan
5) Akses air bersih dan fasilitas sanitasi.
d. Simulasi air yang telah terkontaminasi; mengajak masyarakat untuk melihat
bagaimana kotoran manusia dapat dimakan oleh manusia yang lainnya. Berkaitan
dengan stunting, simulasi mengukur TB balita, LILA Ibu hamil, penimbangan BB
balita, disesuaikan dengan standar. Mengajak masyarakat untuk melakukan diteksi
faktor resiko stunting yang dimiliki dan yang harus di rubah dengan perilaku
mencegah stunting
e. Diskusi Kelompok (FGD); bersama-sama dengan masyarakat melihat kondisi
yang ada dan menganalisanya sehingga diharapkan dengan sendirinya masyarakat
dapat merumuskan apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan.
Pembahasannya meliputi:
1) FGD untuk menghitung jumlah tinja dari seluruh masyarakat yang BAB di
sembarang tempat selama 1 hari, 1 bulan, dan dalam 1 tahunnya.
2) FGD tentang privacy, agama, kemiskinan, dan lain-lain disesuaikan dengan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 112
kondisi di masyarakat yang ditemui.
Berkaitan dengan stunting, secara bersama – sama melihat kondisi faktor resiko
yang dimiliki dan sisa waktu dari saat pemicuan sampai 1000 hari pertama
kelahiran, dapat dihitung apa yang harus dipantau dan berjumlah berapa bagi tiap
individu, serta berapa porsi PMT maupun MPASI yang harus disediakan jika
diserahkan kepada kelompok.
Tabel 8. Kerangka Pikir Pemicuan STBM-Stunting
Input Proses Output Efek Dampak
Stunting Screening perilaku Ada Panitia lokal Ada Penyediaan PMT dan Stunting <
20% ibu hamil dan penyelenggara MPASI Non Subsidi 20%
peran fungsi PMT dan MPASI
masyarakat.
Ada - Pemetaan Masyarakat Bumil melakukan:
BBLR - Transect terpicu oleh
walk elemen
- FGD pemicuan
- Alur STBM-Stunting.
Kontaminasi Ada RTL
- Alur Masalah
Bumil Stunting Ada Target - PMT
KEK Capaian - Tablet tambah darah
90 tablet
- Menjaga kesehatan
Sanitasi diri
dan air - Memberi ASI Eksklusif
bersih - Memberi MPASI
buruk - Memberi Vitamin A
Balita
- Memberi imunisasi
lengkap
- Sanitasi dan Air bersih
layak
C. Elemen Pemicuan dan Faktor Penghambat Pemicuan.
Dalam pemicuan di masyarakat terdapat beberapa faktor/elemen yang harus dipicu.
Target utama yang diharapkan dari pendekatan STBM-Stunting, salah satunya yaitu:
merubah perilaku sanitasi dari masyarakat yang masih melakukan kebiasaan BAB di
sembarang tempat dapat tercapai dan masyarakat terbiasa dengan perilaku untuk
mencegah kejadian stunting.
Secara umum faktor-faktor sebagai elemen yang harus dipicu untuk menumbuhkan
perubahan perilaku sanitasi dan mencegah stunting dalam suatu komunitas,
diantaranya:
Perasaan jijik,
Perasaan malu dan kaitannya dengan privacy seseorang,
Perasaan takut sakit,
Perasaan takut berdosa,
Perasaan tidak mampu dan kaitannya dengan kemiskinan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 113
Berikut ini adalah elemen-elemen yang harus dipicu, dan alat – alat partisipatif yang
digunakan untuk pemicuan faktor-faktor tersebut dalam STBM Stunting seperti tabel
berikut:
Tabel 9. Elemen Pemicuan dan Alat Partisipatif yang Digunakan
Hal yang
Alat yang digunakan
harus dipicu
Rasa jijik Transectwalk
Demo air yang mengandung tinja, untuk digunakan cuci muka,
kumur-kumur, sikat gigi, cuci piring, cuci pakaian, cuci makanan/
beras, wudhu, dll.
Berkaitan dengan stunting:
Melihat dan mengambil piring makan yang tidak dibersihkan
dengan baik, lalu peserta diminta menaruh makanan diatas
piring tersebut .
Bagaimana persaan peserta?
Rasa malu Transect walk (mengelaborasi pelaku BAB sembarangan)
FGD (masalah privasi)
Perhitungan jumlah tinja
Pemetaan rumah warga yang terkena diare dengan didukung
data puskesmas
Berkaitan dengan stunting:
Transect walk (melihat jenis MPASI/PMT rumah tangga, melihat
kondisi sanitasi dapur rumah tangga)
• Diperlihatkan balita kecil karena stunting dan balita
normal.
• Diajukan pertanyaan apa yang ibu berikan untuk MPASI
anak tersebut
FGD
• Bagaimana perasaan ibu balita stunting
• Bagaimana perasaan ibu balita normal.
• Apa yang akan dilakukan ibu balita stunting ?
Alur kontaminasi
Takut sakit FGD:
Perhitungan jumlah tinja
Pemetaan rumah warga yang terkena diare, kecacingan, gizi
kurang, stunting dengan didukung data puskesmas
Kekhawatiran ibu hamil dan ibu memiliki balita jika
mereka/anaknya sakit dan stunting.
Alur kontaminasi
Aspek agama Mengutip hadits atau pendapat-pendapat para ahli agama yang
relevan dengan perilaku manusia yang dilarang karena merugikan
manusia itu sendiri.
Berkaitan dengan stunting:
Dihadapkan apa yang dilakukan ibu balita stunting dan apa yang
dijelaskan oleh agama.
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 114
Hal yang
Alat yang digunakan
harus dipicu
juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. [QS. Al-Baqarah: 233].
Bagaimana perasaan ibu ?
Kemiskinan Membandingkan kondisi di desa/dusun yang bersangkutan dengan
masyarakat “termiskin” seperti di beberapa wilayah di Indonesia.
Berkaitan dengan stunting:
Dihadapkan dua orang ibu terdiri, kaya dengan balita normal , dan miskin
dengan balita stunting.
Apakah orang miskin harus mempunyai balita dengan risiko stunting ?
Biaya Subsidi Jelaskan prinsip STBM-Stunting tidak membawa subsidi
Gengsi dan Gali jenis makanan lumat yang biasa diberikan pada anak (bubur
Malu sumsum kacang ijo, bubur beras merah, bubur kentang saos pepaya,
bubur kangkung saos jeruk).
Gali jenis makanan lembek (Nasi Tim Kangkung Soos Pepaya, Tim
Jagung muda saos melon, Nasi Tim Tempe, Nasi Tim beras merah,
Tim Manado Pisang).
Coba mana yang di senangi anak?
Tanyakan makanan mana yang lebih bergizi untuk anak?
Apa yang akan ibu lakukan agar makan makanan yang lebih bergizi?
Tidak Ada Munculkan natural leader, yang bersedia menjadi pengelola,
Tokoh penyelenggara MPASI – PMT secara kelompok.
Panutan
Dalam memicu elemen-elemen di atas, dalam suatu komunitas biasanya ada juga
faktor-faktor penghambat pemicuan. Salah satunya adalah bahwa masyarakat sudah
terbiasa dengan subsidi, sementara dalam pendekatan STBM-Stunting tidak ada unsur
subsidi sama sekali. Berikut adalah beberapa hal yang biasanya menjadi penghambat
pemicuan di masyarakat, dengan alternatif solusi untuk mengurangi atau mengatasi
faktor penghambat tersebut.
Tabel 10. Faktor Penghambat Pemicuan dan Solusi yang Disarankan
Hal-hal yang Menjadi Penghambat
Solusi
Pemicuan di Masyarakat
Kebiasaan dengan subsidi / bantuan Jelaskan dari awal bahwa kita tidak punya apa-
apa, kita tidak membawa bantuan
Faktor gengsi; malu untuk Gali model-model jamban menurut masyarakat
membangun jamban yang sangat dan jangan memberikan 1 pilihan model
sederhana (ingin jamban permanen); jamban
malu memberikan ASI dan makanan Gali makanan yang diberikan kepada
anak/balita (ASI dan makanan
tambahan dengan gizi berimbang
tambahannya/PMBA) dan ajak masyarakat
karena susu formula terkesan secara menemukan makanan yang sehat yang ada di
ekonomi lebih kaya. sekitarnya, mudah diperoleh, murah, dan
bergizi.
Tidak ada tokoh panutan Munculkan natural leader, jangan mengajari
dan biarkan masyarakat mengerjakannya
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 115
Hal-hal yang Menjadi Penghambat
Solusi
Pemicuan di Masyarakat
sendiri.
Stunting adalah karena keturunan Jelaskan bahwa stunting bukan karena
keturunan tetapi dampak dari berbagai faktor.
Ajak diskusi untuk mengidentifikasi faktor
resiko stunting misalnya menggunakan
Diagram F STBM-Stunting.
Stunting adalah anak cebol. Jelaskan bahwa Stunting tidak sama dengan
anak cebol.
Stunting tidak berdampak sehingga Gunakan diagram F STBM-Stunting untuk
tidak perlu dikhawatirkan. menjelaskan penyebab dan dampak stunting
sehingga masyarakat perlu bertindak untuk
mencegah stunting.
D. Langkah-langkah Pemicuan di Komunitas
a. Perkenalan dan Penyampaian Tujuan
Perkenalkan terlebih dahulu anggota tim pemicu dan sampaikan tujuan bahwa tim ingin
“melihat dan belajar” tentang kondisi sanitasi dan gizi dari kampung tersebut. Jelaskan
dari awal bahwa kedatangan tim bukan untuk memberikan penyuluhan apalagi
memberikan bantuan. Tim hanya ingin melihat dan mempelajari bagaimana kehidupan
masyarakat, bagaimana masyarakat mendapat air bersih, bagaimana masyarakat
melakukan kebiasaan buang air besar, dan lain-lain termasuk aktifitas yang
berhubungan dengan kebiasaan ibu hamil, melahirkan hingga menyusui dan merawat
bayi dan balita.
Tanyakan kepada masyarakat apakah mereka mau menerima tim dengan maksud dan
tujuan yang telah disampaikan?
b. Bina Suasana
Untuk menghilangkan “jarak” antara tim pemicu dan masyarakat sehingga proses
fasilitasi berjalan lancar, sebaiknya lakukan pencairan suasana. Pada saat itu temukan
istilah setempat untuk “tinja” (misalnya “tai”, dll), BAB (ngizing, naeng, dll.), stunting
(pendek, dll.).
Istilah lain yang perlu disepakati bersama masyarakat sebelum pemicuan berkaitan
dengan STBM-stunting adalah sebagai berikut:
Stunting, diukur TB menurut umur, dibandingkan standar, bila < -2SD disebut balita
pendek.
Bumil, LILA < 23,5 cm disebut Bumil KEK.
Pertumbuhan balita terganggu bila 3 kali penimbangan bulanan tidak naik beratnya.
BBRL bila kurang 2500 gram saat lahir.
PMT Bumil berisiko BBLR, perlu penyuluhan PMT.
Anemia bila kadar Hb darah kurang 11 g / dL
ASI Eklusif pemberian ASI saja sampai umur 6 bulan
MPASI, makanan berbentuk lunak maupun dewasa selain ASI sampai usia 24
bulan.
c. Analisa Partisipatif dan Pemicuan
Memulai proses pemicuan di masyarakat, yang diawali dengan analisa partisipatif
misalnya melalui pembuatan peta desa/dusun/ kampung yang akan menggambarkan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 116
wilayah BAB masyarakatnya termasuk pemetaan kejadian stunting (setelah istilah
stunting disepakati masyarakat).
1) Pemetaan (rumah/kk, anggota keluarga, bumil, baduta)
3. Menghitung tinja
2) Alur Kontaminasi (Oral Fecal) dan Stunting
3) Transect Walk
4) Simulasi Air yang Telah Terkontaminasi
5) Diskusi Kelompok (FGD)
FGD untuk memicu rasa “malu” dan hal-hal yang bersifat “pribadi”
FGD untuk memicu rasa “jijik”, “takut sakit”, “gengsi”, dan “takut masa depan anak
tidak cerah”.
FGD untuk memicu hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan (Contohnya dalam
komunitas yang beragama Islam)
FGD Menyangkut Kemiskinan. FGD ini biasanya berlangsung ketika masyarakat
sudah terpicu dan ingin berubah, namun terhambat dengan tidak dana uang untuk
membangun jamban, memberikan makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak, atau
ke posyandu untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memantau
pertumbuhan anak.
Seluruh langkah atau proses dari alat/tools/metode di atas disediakan dalam Lembar
Panduan tersendiri dan menjadi bagian dari Modul ini (Lihat LP 4.4 beserta Lampiran
4.4.1).
POKOK BAHASAN 3: PASKA PEMICUAN
A. Cara Membangun Ulang Komitmen
Dimaksudkan untuk meningkatnya motivasi masyarakat melaksanakan rencana
kegiatan yang mereka telah susun pada saat memberikan komitmen di kegiatan
pemicuan sebelumnya. Hasil akhir dari tahap ini adalah disepakatinya komitmen semua
pihak untuk keberhasilan pencapaian rencana kegiatan masyarakat yang lebih luas.
Proses kegiatan diawali dengan mempersilahkan wakil masyarakat untuk
mempresentasikan kondisi sanitasi dan gizi/stunting di komunitasnya dan rencana
mereka ke depan. Selanjutnya kita melakukan penegasan untuk meningkatkan motivasi
masyarakat. Misalnya: mengajak peserta memberi tepuk tangan, menegaskan tentang
tanggal bebas dari BAB terbuka dan penurunan kejadian stunting untuk setiap
komunitas, menunjukkan para natural leader yang akan memotori gerakan masyarakat,
dll.
Pada akhir kegiatan berikanlah penegasan-penegasan untuk membangun komitmen
bersama semua pihak dalam upaya pencapaian bebas dari BAB terbuka dan bebas dari
kejadian stunting di tingkat yang lebih luas.
Hasil komitmen yang telah disepakati bersama masyarakat, diserahkan oleh perwakilan
kelompok masyarakat kepada pejabat berwenang di daerah (Desa-Kecamatan-
Puskesmas dan bahkan sampai pemerintah kabupaten) untuk dilakukan tindak lanjut
sesuai dengan rencana. Diharapkan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti sesuai
proses yang telah terjadi dan dapat menghasilkan keluaran yang diharapkan oleh
masyarakat.
B. Pilihan Teknologi Sanitasi untuk 8 Pilar STBM-Stunting
Pencapaian Desa/Kelurahan STBM dengan kondisi sanitasi total yang mencakup 5 pilar
STBM dan 3 pilar pencegahan stunting akan diikuti dengan pencapaian akses sarana
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 117
dan prasarana sanitasi dan penurunan kejadian stunting di masyarakat. Pencapaian
sarana sanitasi dan penurunan kejadian stunting di masyarakat akan mulai dengan
teknologi yang paling sederhana hingga teknologi yang canggih dan terkelola dengan
baik. Pilihan teknologi sanitasi untuk 5 pilar STBM dan 3 pilar untuk penurunan kejadian
stunting ini berprinsip harus sesuai dengan standar kesehatan, mudah, dan terjangkau
oleh masyarakat.
Dalam pemilihan opsi teknologi yang ada, masyarakat harus memahami tangga sanitasi
dan stunting. Tangga sanitasi akan membantu masyarakat untuk mempraktikkan
kebiasaan pola hidup bersih dan sehat. Dengan bantuan alat sederhana hingga alat
lebih canggih dan permanen. Sebagai contoh, untuk pilar 1, masyarakat naik dari
kebiasaan awal yang masih BAB sembarangan hingga mencapai kondisi berperilaku
higienis dan saniter dengan BAB di jamban sehat dan permanen. Pilar 2, masyarakat
berubah perilakunya dari tidak mencuci tangan hingga mencuci tangan pakai air dan
sabun, dan naik lagi misalnya dengan melakukannya di wastafel yang permanen. Pilar
7 misalnya masyarakat naik dari biasanya tidak memberikan makanan dengan gizi
berimbang kepada PMBA yang sesuai untuk umur anak menggunakan teknologi
pengolahan makanan sederhana. Begitupun dengan pilar-pilar lainnya yang
menunjukkan adanya perubahan dan peningkatan perilaku menjadi lebih baik.
Tangga Sanitasi dan Gizi untuk 8 Pilar STBM-Stunting
Tangga sanitasi dan gizi untuk 8 pilar STBM-Stunting merupakan tahap perkembangan
yang dilakukan masyarakat, mulai dari menggunakan sarana yang sangat sederhana
sampai sarana yang sangat layak dilihat dari aspek kesehatan, keamanan dan
kenyamanan bagi penggunanya. Misalnya untuk sanitasi, mulai dari BAB sembarangan
hingga BAB di jamban yang sehat dan layak, dari tidak memiliki fasilitas cuci tangan di
toilet hingga memiliki wastafel. Untuk stunting, misalnya dari tidak memperhatikan
kebersihan alat makan hingga memiliki alat makan dan masak yang sehat dan layak.
Dalam STBM Stunting, masyarakat tidak diminta atau disuruh untuk membuat sarana
sanitasi dan penurunan kejadian stunting tetapi hanya mengubah perilaku sanitasi dan
faktor penyebab stunting mereka. Namun pada tahap selanjutnya ketika masyarakat
sudah mau merubah kebiasaan BAB-nya dan kejadian penurunan stunting, sarana
sanitasi dan stunting menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan.
Seringkali pemikiran masyarakat akan sarana sanitasi adalah sebuah bangunan yang
kokoh, permanen, dan membutuhkan biaya yang besar untuk membuatnya. Pemikiran
ini sedikit banyak menghambat animo masyarakat untuk membangun sarana sanitasi,
seperti jamban, karena alasan ekonomi dan lainnya sehingga kebiasaan masyarakat
untuk buang air besar pada tempat yang tidak seharusnya tetap berlanjut. Disisi lain
untuk Ibu-Ibu yang punya Bayi dalam menggunakan kebiasaan ASI, PMT dan lain
sebagainya dalam program gizi seimbang masih dianggap mahal dan harus dari luar.
C. Membangun Jejaring Layanan Penyediaan Sanitasi dan Gizi
Setelah masyarakat terpicu dan mau berubah, secara otomatis masyarakat akan
membutuhkan sarana sanitasi yang higiene dan layak serta merubah kebiasaan menuju
gizi seimbang dan kebiasaan lain dalam penurunan kejadian stunting. Perlu dicatat
bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan keuangan untuk
menyediakan sarana sanitasi dan penurunan kejadian stunting yang dibutuhkannya.
Oleh karena itu, setelah dilakukan pemicuan, wirausaha STBM-Stunting diundang untuk
menyediakan opsi-opsi pilihan sarana sanitasi dan perubahan perilaku hidup bersih dan
sehat lainnya yang dibutuhkan masyarakat dengan proses pembiayaan yang juga
sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 118
Disamping itu perlunya membangun jejaring layanan penyediaan sanitasi dan
penurunan stunting untuk mensinergikan potensi-potensi yang ada di masyarakat dalam
percepatan pencapaian rencana yang sudah disusun oleh masyarakat, hal ini bisa juga
dilakukan dan dibantu oleh wirausaha STBM-Stunting yang ada dan muncul di
masyarakat, jika belum muncul para wirausahawan di bidang sanitasi dan untuk
penurunan kejadian stunting, hal ini bisa diawali dan difasilitasi oleh dinas kesehatan
setempat yang sudah mendapatkan ketrampilan terkait wirausaha STBM.
Keberadaan wirausaha STBM akan mendekatkan suplai sanitasi dan penurunan
kejadian stunting kepada masyarakat dan mempermudah perwujudan niat mereka
untuk merubah perilaku.
D. Pendampingan dan Monitoring,
Pendampingan dilaksanakan untuk memperkuat keyakinan masyarakat tentang
komitmen yang telah dibangun melalui perubahan perilaku secara kolektif yang
diaplikasikan dengan upaya individu untuk mewujudkannya. Disamping itu, dalam
keadaan tertentu masyarakat membutuhkan mitra untuk melakukan dialog dalam upaya
mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Pada saat itu diperlukan
pendampingan untuk melakukan dialog dan mewujudkan komitmen masyarakat. Oleh
karena itu, fasilitator datang kembali untuk mendampingi masyarakat melakukan
monitoring terhadap progress dari rencana tindak lanjut yang mereka buat.
Pendampingan dilakukan berdasarkan komitmen dengan masyarakat dan disesuaikan
dengan proses alur pemberdayaan.
Keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan apakah mempengaruhi perubahan yang
diinginkan atau tidak, tidak akan terjadi apabila kita tidak melakukan monitoring.
Informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses dan pendekatan
kegiatan, dan bahan perencanaan ke depan.
Secara khusus untuk monitoring dan evaluasi program STBM melalui Sistem Informasi
Monitoring dilaksanakan secara umum melalui tahapan, yaitu pengumpulan data dan
informasi, pengolahan dan analisis data dan informasi, dan pelaporan dan pemberian
umpan-balik. Tahapan ini terjadi di masing-masing tingkatan.
Monitoring program STBM stunting sedapat mungkin dapat dilakukan secara mandiri
dan partisipatori oleh masyarakat sendiri, dan diharapkan peran aktif dari natural leader
yang muncul dan organisasi masyarakat seperti PKK, kelompok dasa wisma, dan
lainnya. Namun demikian tetap diharapkan peran aktif dari petugas PUSKESMAS/
Sanitarian sebagai fasilitator dan katalisator di tingkat kecamatan/desa dalam
mengelola data dan informasi hasil monitoring kegiatan kesehatan lingkungan ini. Bila di
tingkat kabupaten terdapat proyek terkait STBM Stunting sedang berjalan, fungsi
monitoring ini akan diperkuat dengan memanfaatkan sumber daya tenaga
konsultan/fasilitator di tingkat kabupaten untuk melakukan alih pengetahuan dan
pembinaan, baik terhadap para petugas PUSKESMAS/Sanitarian maupun langsung
kepada masyarakat (natural leader/ organisasi masyarakat yang berperan aktif).
Adapun alat yang digunakan dalam proses monitoring, diantaranya:
a. Pemetaan dan skoring pemetaan, untuk melihat akses masyarakat terhadap
tempat-tempat BAB (dengan cara membandingkan antara akses sebelum pemicuan
dan akses yang terlihat paska pemicuan dan tindak lanjut masyarakat).
b. Rating Scale atau Convinient, yang bertujuan untuk:
- melihat dan mengetahui apa yang dirasakan masyarakat (bandingkan antara
yang dirasakan dulu ketika BAB di sembarang tempat dengan yang dirasakan
sekarang ketika sudah BAB di tempat yang tetap dan tertutup).
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 119
- Mengetahui apa yang masyarakat rasakan dengan sarana sanitasi yang
dipunyai sekarang, dan hal lain yang ingin mereka lakukan Hal ini berkaitan
dengan tangga sanitasi dimasyarakat. Langkah kerja dari masing-masing alat
tersebut dapat dilihat (untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan)
dalam lampiran “PANDUAN FASILITASI DI TINGKAT KOMUNITAS”
- Dalam hal rating skale, dilihat testimoni hasil penurunan faktor resiko, apa yang
dirasakan dibandingkan sebelumnya
Adapun gambaran sederhana dari pelaksanaan monitoring program STBM seperti pada
tabel 11 berikut.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 120
Tahap 1 2 3 4 5 6
Kabupaten/
Tingkatan Desa/ Kelurahan Kecamatan Provinsi Pusat
Kota
Dinas DInas
Pelaku Natural leader/ Kementerian
Fasilitator Staf Puskesmas Kesehatan Kesehatan
pemantauan Komite Kesehatan
Kabupaten/ Kota Provinsi
Workshop review
Konsolidasi data pembelajaran
melalui SMS tahunan dan analisis
Mengkompilasi
update progress gateway komparatif Rakornas STBM:
Melalui pemicuan Analisis data: pencapaian hasil review tahunan dan
pemicuan
masyarakat ataupun Memantau perbaikan kegiatan antar kabupaten/ analisis komparatif
Memverifikasi klaim
secara khusus ada perkembangan dan perencanaan kota pencapaian hasil
STBM dan
Aksi yang upaya untuk pemicuan di kedepan antar propinsi.
melaporkan hasil Disseminasi kepada
dilakukan melakukan masyarakat
verifikasi Feedback kepada lintas program Disseminasi kepada
pengumpulan data Permintaan verifikasi
Feedback temuan staf puskesmas terkait dan sektor lintas program
dasar STBM oleh STBM
Mengirim laporan Disseminasi kepada AMPL terkait dan sektor
kabupaten/ kota
pemantauan via Evaluasi tahunan AMPL
lintas program
SMS kompetitif melalui
terkait dan sektor
AMPL media massa
(contoh J PIP)
Mencatat Konsolidasi untuk
Data dasar Pelaporan
kemajuan dan Penilaian pencapaian MDG.
STBM (misal bulanan.
memperbaharui Pelaporan kinerja per tahun Penilaian kinerja
melalui peta Pelaporan
Pelaporan sosial), berisi
dalam peta sosial bulanan.
tahunan
(Benchmarking) per tahun
terhadap Verifikasi STBM. program sanitasi (Benchmarking)
akses sanitasi di Bahan untuk
perubahan yang kabupaten/kota program sanitasi
masyarakat publikasi
terjadi propinsi.
Tabel 11 Alur pikir tata laksana monitoring dan pelaporan dari masyarakat hingga tingkat pusat
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 121
Pelaksanaan monitoring di tingkat masyarakat/ desa
Pelaksanaan monitoring di tingkat masyarakat akan lebih bertumpu kepada indikator
monitoring yang mudah dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu
sendiri, antara lain terkait:
1. Pengumpulan data dasar terkait indikator 8 pilar perubahan perilaku hidup
bersih dan sehat untuk STBM dan Stunting, yaitu: a) data akses awal jumlah
masyarakat yang memiliki dan menggunakan jamban sehat, memiliki dan
menggunakan jamban tidak sehat, jumlah masyarakat yang masih numpang
ke jamban tetangga atau umum dibedakan menurut jenis jamban sehat dan
tidak sehat, dan terakhir masih BAB di sembarang tempat; jumlah anak
stunting, gizi buruk, dan jumlah warga yang ke posyandu b) data akses awal
jumlah keluarga (termasuk anggota keluarga di dalamnya) yang telah
terbiasa cuci tangan pakai sabun pada waktu-waktu kritis dan pergi ke
posyandu secara rutin; c) data akses awal jumlah keluarga yang telah
mengelola air minumnya dengan aman dan mengelola
makanan/minumannya sesuai standar gizi; d) data akses awal jumlah
keluarga yang telah mengelola sampahnya dengan aman; e) data akses
awal jumlah keluarga yang telah mengelola limbah cair rumah tangganya
dengan aman.
2. Proses pemicuan perubahan perilaku Buang Air Besar masyarakat dan
Pencegahan Stunting.
Indikator yang direkam antara lain: a) peningkatan akses masyarakat kepada
penggunaan sarana jamban sehat; b) kebersihan lingkungan sekitar rumah
keluarga; c) peningkatan perubahan perilaku pilar lainnya; dan d) rutinias ke
posyandu.
3. Pendataan tukang yang terkait dengan jasa dan layanan sanitasi dan gizi.
Pendataan ini bertujuan untuk menjaring informasi jumlah tukang yang
beredar di desa bersangkutan yang memiliki pengalaman dan/ atau
ketrampilan membangun/ memperbaiki sarana jamban, serta jumlah orang
yang berpengalaman atau menyediakan jasa terkait dengan gizi masyarakat
misalnya memproduksi dan menjual makanan tambahan yang sehat dan
bergizi.
Berikut dibawah ini disajikan beberapa model pelaksanaan monitoring yang dapat
dilakukan di tingkat masyarakat.
Table 12: Model Pelaksanaan Monitoring di Masyarakat
Pelaku Cara Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan
Monitoring perkembangan perubahan perilaku BAB dan pembuangan kotoran
anak batita
Masyarakat Persiapan: Setiap saat ada
Pihak kabupaten/ kecamatan/ desa perubahan perilaku
menyediakan kertas spot berwarna (merah, yang terjadi pada
kuning, hijau), dengan yang mudah terlihat komunitas tersebut.
dari jarak pandang cukup jauh, misal: bentuk
bulat dengan diameter 15 cm; bentuk
bujursangkar dengan ukuran 15 cm X 15 cm.
Menginformasikan penggunaan kertas
berwarna kepada masyarakat setelah proses
pemicuan awal atau saat monitoring lanjutan.
Kertas merah (jamban numpang), kuning
(jamban blm sehat), hijau (jamban sehat).
Untuk aspek PHBS lain, seperti cuci tangan,
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 122
Pelaku Cara Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan
pengelolaan dan penyimpanan air minum dan
makanan, pengelolaan limbah RT dapat
mengikuti pola monitoring mandiri untuk
perilaku BAB di jamban. Untuk efektivitas
monitoring dapat menggunakan “kartu sehat”
Pelaksanaan Monitoring:
Masyarakat yang telah berupaya berubah
perilaku untuk tidak BAB di sembarang
tempat (termasuk membuang kotoran anak
batita tidak sembarangan), menempelkan
tanda kertas spot di depan rumah mereka
pada tempat yang tampak dari pandangan
orang yang berdiri di depan atau melalui
rumah tersebut. Warna yang ditempel sesuai
kondisi perkembangan upaya perubahan
perilaku mereka.
Pada kertas tersebut dapat dituliskan tanggal
mereka melakukan perubahan tersebut.
Apabila pada keluarga tertentu ada
peningkatan perubahan perilaku dengan
ditandai perubahan warna kertas spot yang
ditempel. Tempel warna baru diatas warna
lama, sehingga informasi warna awal masih
ada.
Natural leader atau komite secara berkala
memperbaharui informasi tersebut dalam
peta masyarakat (tanpa mengganggu
informasi baseline)
Monitoring perkembangan perubahan perilaku kunjungan ke Posyandu
Masyarakat Persiapan: Setiap saat ada
Pihak kabupaten/ kecamatan/ desa perubahan perilaku
menyediakan kertas/stiker yang mudah yang terjadi pada
terlihat dari jarak pandang cukup jauh. komunitas tersebut.
Menginformasikan penggunaan stiker/kertas
berwarna kepada masyarakat setelah proses
pemicuan awal atau saat monitoring lanjutan.
Stiker A diberikan bagi Ibu yang rutin ke
Posyandu dan berhasil memberikan ASI
Ekslusif, Stiker B diberikan bagi ibu hamil
yang rutin ke posyandu dan telah
mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai
yang disyaratkan. Stiker C diberikan kepada
ibu dengan anak Baduta yang memberikan
PMBA bergizi baik.
Pelaksanaan Monitoring:
Menempelkan stiker/kertas di rumah warga
yang telah melakukan perubahan dan
memenuhi syarat tersebut di atas.
Apabila pada keluarga tertentu ada
peningkatan perubahan perilaku dengan
ditandai penempelan stiker/kertas.
Natural leader atau komite secara berkala
memperbaharui informasi tersebut dalam
peta masyarakat (tanpa mengganggu
informasi baseline)
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 123
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa monitoring di tingkat masyarakat ini
menggunakan pendekatan partisipatori dan mengangkat peran aktif masyarakat
untuk melakukan monitoring mandiri. Oleh karena itu, penting sekali bahwa selama
proses kegiatan STBM, fasilitator kabupaten membantu meningkatkan kapasitas
masyarakat untuk melakukan monitoring mandiri melalui on the job training.
Pelaksanaan monitoring di tingkat puskesmas/ kecamatan
Pelaksanaan monitoring di tingkat puskesmas/ kecamatan akan lebih bertumpu
kepada mengumpulkan perkembangan informasi di tingkat desa dan menjaring
indikator monitoring yang terjadi di tingkat puskemas/ kecamatan, antara lain sebagai
berikut:
Tabel 13: Model Pelaksanaan Monitoring di Tingkat Puskesmas
Pelaku Cara Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan
1. Perekaman monitoring perkembangan perubahan perilaku BAB &
pembuangan kotoran anak batita (kemajuan pemicuan), perilaku CTPS,
serta pilar lainnya
Fasilitator Persiapan: Perekaman data
pemicu Pihak kecamatan/ puskesmas menyiapkan dan dasar (baseline) di
(Kecamatan/ memahami pengisian format monitoring awal dan kemajuan
Puskesmas) perkembangan perubahan perilaku pilar-pilar hasil pemicuan
STBM (pilar 1 hingga pilar 5). dilakukan bulanan
(misal: minggu ke-
Contoh Pelaksanaan monitoring: empat setiap
Mengacu kepada peta sosial masyarakat, bulannya)
informasi perkembangan hasil pemicuan (akses
masyarakat kepada jamban) dipindahkan
kedalam format.
Melakukan kunjungan ke rumah tangga yang
telah melakukan perubahan (berdasarkan
perkembangan data pada peta sosial) untuk
mengamati kondisi dan pemeliharaan jamban
dan lingkungan sekitarnya (lihat panduan
transect walk).
Penting: Monitoring perkembangan perubahan
perilaku masyarakat terkait kebiasaan BAB,
sekaligus sebagai kegiatan verifikasi ODF per
rumah tangga, yang digunakan sebagai dasar
verifikasi status ODF suatu komunitas.
2. Monitoring status ODF yang dicapai suatu komunitas (Verifikasi ODF)
Tim Persiapan: Sebaiknya dilakukan
kecamatan Masyarakat melalui natural leader atau komite begitu menerima
bersama menginformasikan pihak Puskesmas untuk informasi dari
masyarakat. dilakukan verifikasi status ke-ODF-an mereka masyarakat
(akan lebih baik bila penginformasian dilakukan bersangkutan
melalui surat pernyataan yang diketahui oleh
kepala desa).
Tim kabupaten menyiapkan stiker atau papan
ODF.
Pelaksanaan monitoring:
Tim kecamatan melakukan pengecekan
informasi total masyarakat yang sudah berubah
perilakunya. Dengan alat bantu peta sosial dan
ceklist jamban, tim mengunjungi rumah
masyarakat dan mencocokkan warna kertas spot
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 124
Pelaku Cara Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan
(kaitkan dengan proses monitoring no.1).
Rekaman hasil verifikasi dicantumkan dalam
format LB-2.
Tim melakukan penilaian terhadap total akses
masyarakat. Hasilnya diinformasikan kepada
masyarakat. Bila telah mencapai 100% akses,
tim dapat menempelkan stiker atau
menempatkan papan ODF dengan diisi tanggal
kapan mereka mencapai ODF dan verifikasi
dilakukan.
3. Monitoring status Desa STBM yang dicapai suatu komunitas (Verifikasi
Desa STBM)
Tim Persiapan: Begitu menerima
kecamatan Masyarakat melalui natural leader atau komite informasi dari
bersama menginformasikan pihak Puskesmas untuk masyarakat
masyarakat. dilakukan verifikasi status ke-STBM-an mereka bersangkutan
(akan lebih baik bila penginformasian dilakukan
melalui surat pernyataan yang diketahui oleh
kepala desa).
Tim kabupaten menyiapkan stiker atau papan
pencapaian Desa STBM.
Pelaksanaan monitoring:
Tim kecamatan melakukan pengecekan
informasi total masyarakat yang sudah berubah
perilakunya. Dengan alat bantu peta sosial dan
ceklist capaian 5 pilar STBM, tim mengunjungi
rumah masyarakat dan mencocokkan warna
kertas spot (kaitkan dengan proses monitoring
no.1).
Rekaman hasil verifikasi dicantumkan dalam
format rekam pilar-1 sampai pilar-5 STBM.
Tim melakukan penilaian terhadap total akses
masyarakat. Hasilnya diinformasikan kepada
masyarakat. Bila telah mencapai 100% akses
kelima pilar STBM, tim dapat menempelkan
stiker atau menempatkan papan Desa STBM
dengan diisi tanggal kapan mereka mencapai
status tersebut dan verifikasi dilakukan.
4. Investasi jamban oleh masyarakat
Fasilitator Persiapan:
pemicu Menyiapkan dan memahami cara pengisian format.
(Kecamatan/
Pelaksanaan:
Puskesmas)
Kegiatan ini dapat dilaksanakan saat fasilitator
pemicu memperbaharui (updating) informasi
kemajuan pemicuan.
Pada saat kunjungan ke rumah tangga, dapat
menanyakan kepada keluarga bersangkutan
perkiraan biaya untuk membangun jamban.
(untuk membantu dapat melakukan perkiraan
bahan yang digunakan dan tenaga yang
dikeluarkan)
5. Pendataan tukang terkait jasa dan layanan sanitasi
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 125
Pelaku Cara Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan
Fasilitator Persiapan:
pemicu Menyiapkan dan memahami cara pengisian format.
bekerja
Pelaksanaan:
sama
dengan Pendataan awal tentang tukang yang ada di
natural komunitas/ desa tersebut sebagai data dasar,
leader (NL)/ dilakukan selang 1 – 2 minggu setelah pemicuan
komite awal,
Pembaharuan pendataan tukang dilakukan
setiap 3 bulan, baik ada pengurangan (karena
pindah atau bekerja diluar) atau penambahan
jumlah tukang.
6. Monitoring mandiri terhadap dampak yang dirasakan
Masyarakat Persiapan: Minimal 6 bulan
bekerja Masyarakat membuat tulisan gambaran kondisi setelah ODF
sama masyarakat sebelum intervensi (pemicuan awal)
dengan dilakukan
pihak
puskesmas/ Pelaksanaan monitoring:
kecamatan/ Masyarakat membuat tulisan perubahan kondisi
kabupaten masyarakat yang dirasakan setelah intervensi
(pemicuan awal) dilakukan.
Hasil tulisan masyarakat ini dapat didokumentasi
secara elektornik dan dipublikasi dalam media
daerah lokal hingga situs AMPL.
Tim Persiapan: Berkala per triwulan
kecamatan Membuat pemberitahuan kepada setiap desa
agar mempersiapkan hasil capaian kegiatan (pada pertemuan
program sanitasi di masing-masing wilayah regular yang ada di
kecamatan)
Pelaksanaan monitoring:
Kegiatan review dan sharing hasil capaian
program sanitasi dapat dilakukan melalui forum
komunikasi tingkat kecamatan
Kegiatan review dan sharing ini dapat diikutkan/
dititipkan dalam kegiatan rutin di tingkat
kecamatan yang meng-agenda-kan pertemuan
kemajuan desa
7. Pendataan toko dan produsen produk sanitasi
Tim Persiapan: Pendataan
puskesmas/ Menyiapkan dan memahami cara pengisian dilakukan secara
kecamatan format pendataan toko dan produsen produk berkala per triwulan
sanitasi
Pelaksanaan:
Tim mengidentifikasi dan memetakan toko
bangunan dan produsen produk sanitasi yang
ada di wilayah kerja Puskesmas/ kecamatan
bersangkutan
Tim membagi tugas kunjungan ke toko
bangunan dan/atau produsen produk sanitasi
Petugas mewawancarai pemiliki toko dan/atau
produsen produk sanitasi dan mengisi informasi
yang dijaring sesuai dengan format LT-2A dan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 126
Pelaku Cara Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan
2B.
8. Pendataan kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building)
Tim Persiapan:
Puskesmas/ Menyiapkan dan memahami cara pengisian
kecamatan format pendataan kegiatan peningkatan
kapasitas (format LT-5)
9. Monitoring institusionalisasi sistem monitoring
Pihak Puskesmas/ kecamatan mencatat dan
Tim
mengkompilasi data komunitas yang
Puskesmas/
menggunakan peta sosial atau instrumen lainnya
kecamatan
dalam memonitor pencapaian ODF dan perilaku
cuci tangan pakai sabun oleh seluruh
masyarakat
10. Monitoring Kerutinan Kunjungan Ibu Hamil dan Balita ke Posyandu
Tim Persiapan: Pendataan
Puskesmas/ dilakukan setiap
kecamatan Menyiapkan dan memahami cara pengisian bulan pada saat
format pendataan kunjungan ke posyandu posyandu (tim
Pelaksanaan: Puskesmas
Tim mengisi format yang diberikan mengkoordinir data
Tim mengisi buku KIA ibu hamil dan anak. yang disiapkan oleh
Posyandu).
10. Monitoring Konsumsi PMBA dan gizi ibu hamil
Tim Persiapan: Pendataan
Puskesmas/ dilakukan setiap
kecamatan Menyiapkan dan memahami cara pengisian bulan pada saat
format monitoring. posyandu (tim
Pelaksanaan: Puskesmas
Tim mengisi format yang diberikan dengan mengkoordinir data
menanyakan kepada Ibu yang datang ke yang disiapkan oleh
Posyandu terkait PMBA dan gizi ibu hamil. Jika Posyandu).
tidak datang, tim dapat mengisi formal yang
diberikan saat melakukan kunjungan rumah.
Tim mengisi buku KIA ibu hamil dan anak.
Monitoring dan Evaluasi STBM-Stunting
Untuk saat ini monitoring dan evaluasi STBM dan stunting masih dilakukan terpisah.
Untuk STBM, sebagaimana dijelaskan diatas, dilakukan melalui sistem monitoring dan
evaluasi STBM (www.stbm-indonesia.org) yang terhubung dengan berbagai alat bantu
seperti SMS, website, dan aplikasi di android. Untuk gizi, monitoring dan evaluasi
dilakukan melalui SMS dan website SIGIZI (http://gizi.depkes.go.id/sigizi/).
Dengan dimulainya inisitaif untuk mengintegrasikan program STBM dengan program
gizi, diharapkan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dapat segera
dikembangkan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 127
E. Menggali media promosi untuk perubahan perilaku yang berkelanjutan
Selain kegiatan monitoring dan evaluasi, diperlukan berbagai kegiatan lain agar
masyarakat tetap mempraktikkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat. Biasanya
setelah masyarakat terbiasa, masyarakat akan otomatis berubah ke perilaku yang
lebih baik tersebut, namun dalam jangka panjang jika perubahan perilaku tidak terus
dipromosikan, maka sangat mungkin sekali masyarakat akan lupa dan kembali ke
praktik budaya hidup yang tidak sehat.
Promosi bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui iklan, penyebaran
media komunikasi, ataupun melalui kegiatan-kegiatan formal dan informal di
masyarakat.
VIII. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2013 tentang Angka Kecukupan
Gizi Bagi Bangsa Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan
Gizi
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Keluarga Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1955 Tahun 2010 Tentang Standar
Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 3/2014 tentang STBM.
IX. LAMPIRAN (Terlampir)
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 128
MODUL PENUNJANG 1
MEMBANGUN KOMITMEN BELAJAR (BLC)
I. DESKRIPSI SINGKAT
Dalam suatu pelatihan terutama pelatihan dalam kelas (in class training), akan
bertemu sekelompok orang yang belum saling mengenal sebelumnya, dan berasal
dari tempat yang berbeda, dengan latar belakang sosial budaya, pendidikan/
pengetahuan, pengalaman, serta sikap dan perilaku yang berbeda pula. Apabila hal
ini tidak diantisipasi sejak awal pelatihan, kemungkinan besar akan dapat
mengganggu kesiapan peserta dalam memasuki proses pelatihan yang bisa
berakibat pada terganggunya kelancaran dari proses pembelajaran selanjutnya.
Membangun komitmen Belajar (BLC) merupakan salah satu metode atau proses
untuk mencairkan kebekuan tersebut. BLC juga mengajak peserta mampu
mengemukakan harapan harapan mereka dalam pelatihan ini, serta merumuskan
nilai-nilai dan norma yang kemudian disepakati bersama untuk dipatuhi selama
proses pembelajaran. Membuat kontol kolektif dan struktur organisasi kelas. Jadi inti
dari BLC juga adalah terbangunnya komitmen dari semua peserta untuk berperan
serta dalam mencapai harapan dan tujuan pelatihan, serta mentaati norma yang
dibangun berdasarkan perbauran nilai-nilai yang dianut dan disepakati.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu membangun komitmen belajar dalam
rangka menicptakan iklum pembelajaran yang kondusif selama proses pelatihan
berlangsung.
B. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:
1. Mengenal sesama warga pembelajar pada proses pelatihan.
2. Menyiapkan diri untuk belajar bersama secara aktif dalam suasana yang
kondusif.
3. Merumuskan harapan-harapan yang ingin dicapai bersama baik dalam proses
pembelajaran maupun hasil yang ingin dicapai di akhir pelatihan.
4. Merumuskan kesekapatan norma kelas yang harus dianut oleh seluruh warga
pembelajar selama pelatihan berlangsung.
5. Merumuskan kesepakatan bersama tentang kontrol kolektif dalam pelaksanaan
norma kelas.
6. Membentuk organisasi kelas.
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai
berikut:
A. Pokok Bahasan 1: Perkenalan
B. Pokok Bahasan 2: Pencairan (ice breaking)
C. Pokok Bahasan 3: Harapan-harapan dalam proses pembelajaran dan hasil yang
ingin dicapai.
D. Pokok Bahasan 4: Norma kelas dalam pembelajaran.
E. Pokok Bahasan 5: Kontrol kolektof dalam pelaksanaan norma kelas.
F. Pokok Bahasan 6: Organisasi Kelas.
IV. METODE
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 129
Ceramah Tanya jawab, curah pendapat, permainan, diskusi kelompok.
V. MEDIA DAN ALAT BANTU
Bahan tayang, LCD proyektor, komputer, flipchart, spidol, meta plan, kain tempel,
jadwal dan alur pelatihan, norma/tata tertib standar pelatihan, panduan diskusi
kelompok, dan panduan permainan.
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 3 jam pelajaran (T=0
jpl, P=3 jpl, dan PL=0 JPL) @45 menit. Untuk mempermudah proses pembelajaran
dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta, dilakukan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut:
Langkah 1. Pengkondisian (15 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Fasilitator memulai kegiatan dengan melakukan bina suasana dikelas.
b. Fasilitator menyampaikan salam dengan menyapa peserta dengan ramah
dan hangat.
c. Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas mulailah dengan
memperkenalkan diri. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama
lengkap, instansi tempat bekerja, materi yang akan disampaikan.
d. Menggali pendapat pembelajar (apersepsi) tentang building learning
commitment (blc) dengan metode curah pendapat (brainstorming).
e. Menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam BLC dan
menyampaikan tujuan pembelajaran umum dan khusus dari BLC.
f. Menyampaikan alur proses pelatihan.yang akan dilalui selama pelatihan.
2. Kegiatan Peserta
a. Mempersiapkan diri dan alat tulis bila diperlukan.
b. Mengemukakan pendapat atas pertanyaan fasilitator.
c. Memperkenalkan diri dan asal institusinya
Langkah 2. Pembahasan per materi (110 menit)
A. Review Kegiatan BLC (20 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Menjelaskan petunjuk kegiatan-kegiatan (games) yang akan dimainkan.
b. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal
yang masih belum jelas.
c. Memberikan jawaban / menjelaskan lebih detil jika ada pertanyaan yang
diajukan oleh peserta.
2. Kegiatan Peserta
a. Mendengar, mencatat dan mempersiapkan diri mengikuti games yang
akan dimainkan.
b. Mengajukan pertanyaan kepada fasilitator bila masih ada yang belum
dipahami.
c. Melakukan tugas yang diberikan oleh fasilitator.
B. Pendalaman Kegiatan BLC (60 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Meminta kelas dibagi menjadi beberapa kelompok (4 kelompok) dan
setiap kelompok akan diberikan tugas diskusi kelompok, yaitu membahas
harapan, kekhawatiran dan solusi nya di masing-masing kelompok.
b. Menugaskan kelompok untuk memilih ketua, sekretaris dan penyaji.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 130
c. Meminta masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil dikusi untuk
dipresentasikan.
d. Mengamati peserta dan memberikan bimbingan pada proses diskusi.
2. Kegiatan Peserta
a. Membentuk kelompok diskusi dan memilih ketua, sekretaris dan penyaji.
b. Mendengar, mencatat dan bertanya terhadap hal-hal yang masih belum
jelas kepada fasilitator.
c. Melakukan proses diskusi sesuai dengan masalah yang ditugaskan oleh
fasilitator dan menuliskan hasil dikusi pada kertas flipchart untuk
dipresentasikan.
C. Penyajian dan Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok (30 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Dari masing-masing kelompok diminta untuk melakukan presentasi dari
hasil diskusi yang telah dilakukan sebelumnya.
b. Memimpin proses tanggapan (tanya jawab)
c. Memberikan masukan-masukan dari hasil diskusi.
d. Memberikan klarifikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang belum
dimengerti jawabannya
e. Merangkum hasil diskusi.
f. Meminta perwakilan kelas untuk menunjuk seorang ketua kelas dan
sekretarisnya, yang akan memimpin proses membuat komitmen
pembelajaran melalui norma-norma kelas yang disepakati bersama-sama
beserta pembuatan kontrol kolekifnya.
2. Kegiatan Peserta
a. Mengikuti proses penyajian kelas.
b. Berperan aktif dalam proses tanya jawab yang dipimpin oleh fasilitator.
c. Bersama dengan fasilitator merangkum hasil presentasi dari masing–
masing pokok bahasan yang telah dipresentasikan dengan baik.
d. Ketua dan sekretaris kelas secara bersama dengan peserta membuat
kesepakatan (norma) kelas sebagai bentuk komitmen pembelajaran
beserta kontrol kolektif yang disepakati bersama.
Langkah 3. Rangkuman dan Evaluasi BLC (10 Menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Bersama peserta merangkum poin-poin penting dari hasil proses kegiatan
membangun komitmen pembelajaran.
b. Menyimpulkan dan memperjelas norma-norma kelas yang sudah disepakati
bersama peserta..
c. Mengakhiri kegiatan BLC dengan mengucapkan salam dan permohonan
maaf serta memberikan apresiasi dengan ucapan terima kasih kepada
peserta.
2. Kegiatan Peserta
a. Bersama fasilitator merangkum poin-poin penting dari hasil proses kegiatan
membangun komitmen pembelajaran.
b. Mendengar dan menyepakati hasil dari norma kelas yang telah dibuat.
c. Membalas salam fasilitator.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 131
VII. URAIAN MATERI
POKOK BAHASAN 1: PERKENALAN
Pada awal memasuki suatu pelatihan, sering para peserta menunjukkan suasana
kebekuan (freezing), karena belum tentu pelatihan yang diikuti merupakan pilihan
prioritas dalam kehidupannya. Mungkin saja kehadirannya di pelatihan karena terpaksa,
tidak ada pilihan lain, harus menuruti ketentuan / persyaratan. Mungkin juga terjadi, pada
saat pertama hadir sudah memiliki anggapan merasa sudah tahu semua yang akan
dipelajari atau membayangkan kejenuhan yang akan dihadapi. Untuk mengantisipasi
semua itu, perlu dilakukan suatu proses pencairan(unfreezing).
Proses BLC adalah proses melalui tahapan dari mulai saling mengenal antar pribadi,
mengidentifikasi dan merumuskan harapan dari pelatihan ini, sampai terbentuknya
norma kelas yang disepakati bersama serta kontrol kolektifnya. Pada proses BLC setiap
peserta harus berpartisipasi aktif dan dinamis. Keberhasilan atau ketidakberhasilan
proses BLC akan berpengaruh pada proses pembelajaran selanjutnya.
Pada tahap perkenalan fasilitator memperkenalkan diri dan asal usul institusinya
dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian mengajak peserta
untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam memandu peserta
untuk proses perkenalan dengan menggunakan metode yaitu : dalam 5 menit pertama
setiap peserta diminta berkenalan dengan peserta lain sebanyak-banyaknya. Meminta
peserta yang berkenalan dengan jumlah peserta terbanyak, dan dengan jumlah peserta
paling sedikit untuk memperkenalkan teman-temannya. Meminta peserta yang belum
disebut namanya untuk memperkenalkan diri, sehingga seluruh peserta saling
berkenalan, diikuti juga oleh panitia untuk memperkenalkan dirinya.
POKOK BAHASAN 2: PENCAIRAN
Fasilitator menyiapkan kursi sejumlah peserta dan disusun melingkar. Fasilitator meminta
semua peserta duduk di kursi dan satu diantaranya duduk di tengah lingkaran. Peserta
yang duduk di tengah lingkaran diminta memberi aba-aba, agar peserta yang disebut
identitasnya pindah duduk, misalnya dengan menyeru: ”Semua peserta berbaju merah
pindah” Pada keadaan tersebut akan terjadi pertukaran tempat duduk dan saling berebut
antar peserta. Hal tersebut menggambarkan suasana “storming”, atau seperti “badai”
yang merupakan tahap awal dari suatu pembentukan kelompok.
Ulangi lagi, setiap peserta yang duduk di tengah lingkaran untuk menyerukan identitas
yang berbeda, misalnya peserta yang berkaca mata atau yang berbaju batik dan lain-lain.
Lakukan permainan tersebut selama 10 – 15 menit, tergantung situasi dan kondisi.
Fasilitator memandu peserta untuk merefleksikan perasaannya dalam permainan
tersebut serta pengalaman belajar apa yang diperolehnya. Fasilitator membuat
rangkuman bersama-sama peserta, agar terjadi proses yang dinamis.
POKOK BAHASAN 3: HARAPAN-HARAPAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN
DAN HASIL YANG INGIN DICAPAI
Fasilitator membagi peserta dalam kelompok kecil @ 5 – 6 orang, kemudian menjelaskan
tugas kelompok tersebut. Masing-masing kelompok akan menentukan harapan terhadap
pelatihan ini serta kekhawatiran dalam mencapai harapan tersebut. Juga didiskusikan
bagaimana solusi (pemecahan masalah) untuk mencapai harapan tersebut serta
menghilangkan kekhawatiran yang akan terjadi selama pelatihan. Mula-mula secara
individu, kemudian hasil setiap individu dibahas dan dilakukan kesepakatan sehingga
menjadi harapan kelompok.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 132
Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan peserta dari
kelompok lainnya diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan bila ada. Fasilitator
memandu peserta untuk membahas harapan dan kekhawatiran dari setiap kelompok
tersebut sehingga menjadi harapan kelas yang disepakati bersama. Berdasarkan hasil
pemaparan diskusi seluruh kelompok maka disepakati bersama fasilitator untuk
menentukan ketua kelas dan sekretaris yang akan memandu peserta secara bersama-
sama untuk merumuskan norma-norma kelas yang akan disepakati bersama. Peserta
difasilitasi sedemikian rupa agar semua berperan aktif dan memberikan komitmennya
untuk metaati norma kelas tersebut.
Komitmen merupakan keterikatan, keterpanggilan seseorang terhadap apa yang
dijanjikan atau yang menjadi tujuan dirinya atau kelompoknya yang telah disepakati dan
terdorong berupaya sekuat tenaga untuk mengaktualisasinya dengan berbagai macam
cara yang baik, efektif dan efisien. Komitmen belajar/pembelajaran, adalah
keterpanggilan seseorang/ kelompok/ kelas (peserta pelatihan) untuk berupaya dengan
penuh kesungguhan mengaktualisasikan apa yang menjadi tujuan
pelatihan/pembelajaran. Keadaan ini sangat menguntungkan dalam mencapai
keberhasilan individu/ kelompok/ kelas, karena dalam diri setiap orang yang memiliki
komitmen tersebut akan terjadi niat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik
kepada individu lain, kelompok dan kelas secara keseluruhan.
Dengan membangun komitmen belajar maka para peserta akan berupaya untuk
mencapai harapan yang diinginkannya dalam setiap proses pembelajaran. Dalam hal ini
harapan peserta adalah kehendak/ keinginan untuk memperoleh atau mencapai sesuatu.
Dalam pelatihan berarti keinginan untuk memperoleh atau mencapai tujuan yang
diinginkan sebagai hasil proses pembelajaran. Dalam menetukan harapan harus realistis
dan rasional sehingga kemungkinan untuk mencapainya menjadi besar. Harapan jangan
terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Harapan juga harus menimbulkan tantangan atau
dorongan untuk mencapainya, dan bukan sesuatu yang diucapkan secara asal-asalan.
Dengan demikian dinamika pembelajaran akan terus terpelihara sampai proses
pembelajaran berakhir.
POKOK BAHASAN 4: NORMA KELAS DALAM PEMBELAJARAN
Dalam sesi BLC, lebih banyak menggunakan metode games/ permainan, penugasan
individu dan diskusi kelompok, yang pada intinya adalah untuk mendapatkan komitmen
belajar, harapan, norma kelas dan kontrol kolektif. Proses BLC sendiri adalah proses
melalui tahapan dari mulai saling mengenal antar pribadi, mengidentifikasi dan
merumuskan harapan dari pelatihan ini, sampai terbentuknya norma kelas yang
disepakati bersama serta kontrol kolektifnya. Pada proses BLC setiap peserta harus
berpartisipasi aktif dan dinamis. Keberhasilan atau ketidak berhasilan proses BLC akan
berpengaruh pada proses pembelajaran selanjutnya.
Pada kesempatan ini juga fasilitator akan merumuskan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai dalam kegiatan membangun komitmen belajar, sehingga dengan demikian para
peserta dengan sendirinya sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam keberhasilan
pencapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada pelatihan tersebut.
Norma kelas merupakan nilai yang diyakini oleh suatu kelompok atau masyarakat,
kemudian menjadi kebiasaan serta dipatuhi sebagai patokan dalam perilaku kehidupan
sehari hari kelompok/ masyarakat tersebut. Norma adalah gagasan, kepercayaan tentang
kegiatan, instruksi, perilaku yang seharusnya dipatuhi oleh suatu kelompok. Norma
dalam suatu pelatihan,adalah gagasan, kepercayaan tentang kegiatan, instruksi, perilaku
yang diterima oleh kelompok pelatihan, untuk dipatuhi oleh semua anggota kelompok
(peserta, pelatih/ fasilitator dan panitia).
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 133
POKOK BAHASAN 5: KONTROL KOLEKTIF DALAM PELAKSANAAN NORMA
KELAS
Ketua kelas dan sekretaris beserta fasilitator memandu brainstorming tentang sanksi apa
yang harus diberlakukan bagi orang yang tidak mematuhi atau melanggar norma yang
telah disepakati agar komitmen yang dibangun menjadi lebih kuat. Tuliskan hasil
brainstorming di papan flipchart agar bisa dibaca oleh semua peserta. Peserta difasilitasi
sedemikian rupa sehingga aktif dalam melakukan brainstorming, sehingga dapat
dirumuskan sanksi yang disepakati kelas. Kontrol kolektif merupakan kesepakatan
bersama tentang memelihara agar kesepakatan terhadap norma kelas ditaati. Biasanya
ditentukan dalam bentuk sanksi apa yang harus diberlakukan apabila norma tidak ditaati
atau dilanggar.
POKOK BAHASAN 6: ORGANISASI KELAS
Dengan terbangunnya BLC, juga akan mendukung terwujudnya saling percaya, saling
kerja sama, saling membantu, saling memberi dan menerima, sehingga tercipta suasana/
lingkungan pembelajaran yang kondusif.
Fasilitator memandu peserta membuat rangkuman dari semua proses dan hasil
pembelajaran selama sesi ini. Fasilitator memberi ulasan singkat tentang materi yang
terkait dengan BLC. Fasilitator meminta peserta untuk berdiri membentuk lingkaran
sambil berpegangan tangan, dan mengucapkan ikrar bersama untuk mencapai harapan
kelas dan mematuhi norma yang telah disepakati. Dan untuk mengakhiri sesi diminta
kepada peserta secara bersama-sama untuk bertepuk tangan. Fasilitator mengucapkan
salam dan mengajak semua peserta saling bersalaman.
Dengan melakukan building learning commitment (BLC) yang didahului dengan proses
perkenalan dan dilanjutkan proses pencairan (unfreezing / ice breaking) maka akan
didapatkan komitmen peserta dalam melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya
dengan baik berdasarkan dari norma-norma kelas yang dibuat oleh peserta sendiri.
Adapun untuk keberhasilan proses BLC ini diperlukan adanya partisipasi aktif dari
seluruh peserta pelatihan.
VIII. REFERENSI
Munir, Baderal, Dinamika Kelompok, Penerapannya Dalam Laboratorium Ilmu
Perilaku, Jakarta: 2001.
Depkes RI,Pusdiklat Kesehatan, Kumpulan Games dan Energizer,Jakarta: 2004.
LAN dan Pusdiklat Aparatur Kemenkes RI, Buku Panduan Dinamika Kelompok,
Jakarta: 2010.
IX. LAMPIRAN (Terlampir)
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 134
MODUL PENUNJANG 2
ANTI KORUPSI
I. DESKRIPSI SINGKAT
Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak
buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah
menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem
hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini.
Upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan
hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi
seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap
sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat
atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.
Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang
oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya
pemberantasan korupsi– yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan,
dan (2) pencegahan–tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh
pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi perlu disusun Strategi
Komunikasi Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian
Kesehatan sebagai salah satu kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan
Kementerian Kesehatan agar para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Kesehatan terhindar dari perbuatan korupsi.
Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi
adalah dengan memberikan pengertian dan kesadaran melalui pemahaman
terhadap konsep serta penanaman nilai-nilai anti korupsi yang selanjutnya dapat
menjadi budaya dalam bekerja.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami anti korupsi di lingkungan
kerjanya.
B. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti materi ini peserta mampu:
1. Menjelaskan konsep korupsi.
2. Menjelaskan Anti Korupsi.
3. Menjelaskan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
4. Menjelaskan Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran Tindakan Pidana
Korupsi (TPK).
5. Menjelaskan Gratifikasi.
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai
berikut:
A. Pokok Bahasan 1 : Konsep korupsi
a. Definisi korupsi
b. Ciri-ciri korupsi
c. Bentuk/ jenis korupsi
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 135
d. Tingkatan korupsi
e. Penyebab Korupsi
f. Dasar Hukum
B. Pokok Bahasan 2 : Anti Korupsi
a. Konsep Anti Korupsi
b. Nilai-nilai anti korupsi
c. Prinsip-prinsip anti korupsi
C. Pokok Bahasan 3 : Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
a. Upaya pencegahan korupsi
b. Upaya Pemberantasan Korupsi
c. Strategi Komunikasi Anti Korupsi
D. Pokok Bahasan 4 : Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran TPK
a. Laporan
b. Pengaduan
c. Tata Cara Penyampaian Pengaduan
E. Pokok Bahasan 5 : Gratifikasi
a. Pengertian Gratifikasi
b. Aspek Hukum
c. Gratifikasi merupakan Tindak Pidana Korupsi
d. Contoh Gratifikasi
e. Sanksi Gratifikasi
IV. METODE
Ceramah tanya jawab, curah pendapat, latihan kasus.
V. MEDIA DAN ALAT BANTU
Bahan tayang, LCD proyektor, computer, flipchart, spidol, meta plan.
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini sebanyak 2 jam pelajaran (T: 1 jp; P: 1
jp; PL: 0) @ 45 menit untuk memudahkan proses pembelajaran, dilakukan langkah-
langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
Langkah 1 : Pengkondisian (15 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Memperkenalkan diri,
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran.
2. Kegiatan Peserta
a. Mempersiapkan diri dan alat tulis bila diperlukan.
b. Mengemukakan pendapat atas pertanyaan fasilitator.
c. Memperkenalkan diri dan asal institusinya
Langkah 2. Pembahasan per materi (75 menit)
A. Menyampaikan Materi (30 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Menyampaikan paparan semua materi dengan metode ceramah Tanya
jawab dilanjutkan dengan curah pendapat.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 136
2. Kegiatan Peserta
a. Mendengarkan dan berpartisipasi dalam curah pendapat.
b. Menjawab salam.
B. Latihan kasus (30 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Menyampaikan paparan kasus korupsi yang sering terjadi.
b. Membagi peserta ke dalam kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 peserta,
untuk kasus yang sama dikerjakan oleh 2 atau 3 kelompok
c. Meminta meminta wakil dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil
diskusi kelompoknya (hanya satu kelompok untuk satu kasus) dan
kelompok lainnya dengan kasus yang sama dapat memberikan komentar
atau sebagai penyanggah.
d. Mengulas hasil diskusi yang terjadi di dalam tiap penyajian hasil untuk
tiap jenis kasus.
2. Kegiatan Peserta
a. Melakukan diskusi kelompok.
b. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
c. Memperhatikan dan memberikan komentar terhadap penyampaian hasil
kelompok lain.
Langkah 3. Kesimpulan (15 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Menutup melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta
terhadap materi yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran.
b. Fasilitator merangkum poin-poin penting dari materi yang disampaikan.
c. Fasilitator membuat kesimpulan.
2. Kegiatan Peserta
a. Mengajukan pertanyaan atau komentar yang diminta Fasilitator.
b. Menjawab salam.
VII. URAIAN MATERI
POKOK BAHASAN 1 : KONSEP KORUPSI
A. Definisi Korupsi
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” (Fockema Andrea: 1951) atau
“corruptus” (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio”
berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin
tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis)
dan “corruptie/ korruptie” (Belanda).
Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran,
dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.
Ada banyak pengertian tentang korupsi, di antaranya adalah berdasarkan Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan “penyelewengan atau penggelapan uang negara
atau perusahaan, dan sebagainya untuk keperluan pribadi”.
Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali: 1998):
1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/ sogok, memakai kekuasaan untuk
kepentingan sendiri dan sebagainya;
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 137
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang
sogok, dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.
Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak,
berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat
amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur
pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,
menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke
dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.
B. Ciri-ciri Korupsi
Ada 6 ciri korupsi adalah sebagai berikut:
1. dilakukan oleh lebih dari satu orang;
2. merahasiakan motif; ada keuntungan yang ingin diraih;
3. berhubungan dengan kekuasaan/ kewenangan tertentu;
4. berlindung di balik pembenaran hukum;
5. melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum
6. mengkhianati kepercayaan
C. Jenis/Bentuk Korupsi
Berikut ini adalah berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan
oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK: 2006)
Tabel 14. Jenis/Bentuk Korupsi
No Bentuk Korupsi Perbuatan Korupsi
1 Kerugian Keuangan Negara
Secara melawan hukum melakukan perbuatan mem-perkaya diri sendiri atau orang
lain atau korporasi;
Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2 Suap Menyuap
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya;
Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penye-lenggara negara karena
atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam ja-
batannya;
Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan
atau wewenang yang mele-kat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi
hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedu-dukan tersebut;
3 Penggelapan dalam Jabatan
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara
waktu, dengan disimpan karena jabatannya, atau uang/ surat berharga tersebut
diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan
perbuatan tersebut;
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang di-tugaskan menjalankan
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan
adminstrasi;
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang di-tugaskan menjalankan
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak da-pat dipakai barang,
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 138
akta, surat atau daftar yang digu-nakan untuk meyakinkan atau membuktikan di
muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jaba-tannya;
4 Pemerasan
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain se-cara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau
menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi
dirinya sendiri;
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada wak-tu menjalankan tugas,
meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah
merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bu-kan
merupakan utang;
5 Perbuatan Curang
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat ban-gunan, atau penjual
bahan bangunan yang pada waktu me-nyerahkan bahan bangunan, melakukan
perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau
keselamatan negara dalam keadaan perang;
Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan
bangunan, sengaja membiarkan per-buatan curang;
6 Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik lang-sung maupun tidak langsung
dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau perse-waan yang
pada saat dilakukan perbuatan, untuk se-luruh atau sebagian ditugaskan untuk
mengurus atau mengawasinya.
7 Gratifikasi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau peny-elenggara dianggap pemberian
suap, apabila ber-hubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajiban tugasnya.
D. Tingkatan Korupsi
Ada 3 (tiga) tingkatan korupsi seperti uraian di bawah ini
1. Materi Benefit
Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya
sendiri maupun orang kain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling
membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Ini merupakan
bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia.
2. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah
Merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan,
baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya termasuk lembaga
pendidikan tanpa mendapatkan keuntungan materi.
3. Pengkhianatan terhadap kepercayaan (betrayal of trust)
Pengkhianatan merupakan korupsi paling sederhana
Orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya
adalah koruptor.
Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi
Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat atau memanfaatkan jabatan
untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 139
E. Tingkatan Korupsi
Agar dapat dilakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi maka perlu diketahui
faktor penyebab korupsi. Secara umum ada dua penyebab korupsi yaitu faktor internal
dan faktor eksternal.
Berikut adalah faktor-faktor penyebab korupsi:
1. Penegakan hukum tidak konsisten: penegakan hukum hanya sebagai make-up politik,
sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak
menggunakan kesempatan.
3. Langkanya lingkungan yang antikorup: sistem dan pedoman antikorupsi hanya
dilakukan sebatas formalitas.
4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus
mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong
penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat.
5. Kemiskinan, keserakahan: masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena
kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena
serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan
keuntungan.
6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah.
7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi: saat
tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya
diringankan hukumannya.
8. Budaya permisif/ serba membolehkan; tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada
korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri
terlindungi
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengidentifikasi
beberapa sebab terjadinya korupsi, yaitu: aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi,
aspek masyarakat tempat individu, dan korupsi yang disebabkan oleh sistem yang buruk.
1. Aspek Individu Pelaku Korupsi
Korupsi yang disebabkan oleh individu, yaitu sifat tamak, moral kurang kuat menghadapi
godaan, penghasilan kurang mencukupi untuk kebutuhan yang wajar, kebutuhan yang
mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta ajaran-
ajaran agama kurang diterapkan secara benar.
Aspek-aspek individu tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama. Sangatlah ironis,
bangsa kita yang mengakui dan memberikan ruang yang leluasa untuk menjalankan
ibadat menurut agamanya masing-masing, ternyata tidak banyak membawa implikasi
positif terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Demikian pula dengan hidup konsumtif dan sikap malas. Perilaku konsumtif tidak saja
mendorong untuk melakukan tindakan kurupsi, tetapi menggambarkan rendahnya sikap
solidaritas sosial, karena terdapat pemandangan yang kontradiktif antara gaya hidup
mewah di satu sisi dan kondisi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi
masyarakat miskin pada sisi lainnya.
2. Aspek Organisasi
Pada aspek organisasi, korupsi terjadi karena kurang adanya keteladanan dari pimpinan,
tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di pemerintah kurang
memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, serta manajemen yang lebih
mengutamakan hirarki kekuasaan dan jabatan cenderung akan menutupi korupsi yang terjadi
di dalam organisasi.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 140
Hal tersebut ditandai dengan adanya resistensi atau penolakan secara kelembagaan
terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi. Manajemen yang demikian, menutup rapat
bagi siapa pun untuk membuka praktik korkupsi kepada publik.
3. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada
Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada juga turut menentukan, yaitu
nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat yang kondusif untuk melakukan korupsi.
Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa akibat tindakannya atau kebiasaan dalam
organisasinya secara langsung maupun tidak langsung telah menanamkan dan menumbuhkan
perilaku koruptif pada dirinya, organisasi bahkan orang lain.
Secara sistematis lambat laun perilaku sosial yang koruptif akan berkembang menjadi
budaya korupsi sehingga masyarakat terbiasa hidup dalam kondisi ketidaknyamanan dan
kurang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.
4. Korupsi yang Disebabkan oleh Sistem yang Buruk
Sebab-sebab terjadinya korupsi menggambarkan bahwa perbuatan korupsi tidak saja
ditentukan oleh perilaku dan sebab-sebab yang sifatnya individu atau perilaku pribadi yang
koruptif, tetapi disebabkan pula oleh sistem yang koruptif, yang kondusif bagi setiap
individu untuk melakukan tindakan korupsi.
Sedangkan perilaku korupsi, sebagaimana yang umum telah diketahui adalah korupsi
banyak dilakukan oleh pegawai negeri dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan. Tetapi korupsi dalam artian memberi suap,
juga banyak dilakukan oleh pengusaha dan kaum profesional bahkan termasuk Advokat.
Lemahnya tata-kelola birokrasi di Indonesia dan maraknya tindak korupsi baik ilegal
maupun yang ”dilegalkan” dengan aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara negara,
merupakan tantangan besar yang masih harus dihadapi negara ini. Kualitas tata kelola
yang buruk ini tidak saja telah menurunkan kualitas kehidkupan bangsa dan bernegara,
tetapi juga telah banyak memakan korban jiwa dan bahkan ancaman akan terjadinya lost
generation bagi Indonesia.
Dalam kaitannya dengan korupsi oleh lembaga birokrasi pemerintah, beberapa faktor yang
perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut manajemen Sumber Daya Manusia
(SDM) dan penggajian pegawai yang ditandai dengan kurangnya penghasilan, sistem
penilaian prestasi kerja yang tidak dievaluasi, serta tidak terkaitnya antara prestasi kerja
dengan penghasilan.
Korupsi yang disebabkan oleh sistem yang koruptif inilah yang pada akhirnya akan
menghambat tercapainya clean and good governance. Jika kita ingin mencapai pada
tujuan clean and good governance, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang terkait
dengan pembenahan sistem birokrasi tersebut.
Jika awalnya kepentingan bertahan hidup menjadi motif seseorang atau sejumlah orang
melakukan tindak pidana korupsi, pada tahap berikutnya korupsi dimotivasi oleh bangunan
sistem, yang hanya bisa terjadi karena dukungan kerjasama antar sejumlah pelaku korkupsi,
pada berbagai birokrasi sebagai bentuk korupsi berjamaah.
F. Dasar Hukum Tentang Korupsi
Beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 141
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/ MPR/ 1998
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;
4. UU no. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. UU no. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3874); sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20 Th. 2001.
POKOK BAHASAN 2: KONSEP ANTI KORUPSI
A. Anti Korupsi
Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi
berkembangnya korupsi.
Anti korupsi adalah pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana
meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana
menyelamatkan uang dan aset negara.
Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan
sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral dan
kesejahteraan).
B. Nilai-Nilai Anti Korupsi
Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian,
kedisiplinan, pertanggung-jawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan
keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat
dijalankan dengan baik.
Ada sembilan nilai anti korupsi yang cara gampangnya untuk mengingatnya dengan
jembatan keledai “Jupe mandi tangker sebedil” sebagaimana digambarkan pada bagan di
bawah ini
Berikut ini adalah uraian secara rinci untuk tiap nilai anti korupsi
1. Kejujuran
Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan
tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan pegawai,
tanpa sifat jujur pegawai tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono:
2008).
Nilai kejujuran dalam kehidupan dunia kerja yang diwarnai dengan budaya kerja sangat-
lah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana
termasuk dalam kehidupan di dunia kerja. Jika pegawai terbukti melakukan tindakan yang
tidak jujur, baik pada lingkup kerja maupun sosial, maka selamanya orang lain akan
selalu merasa ragu untuk mempercayai pegawai tersebut.
Sebagai akibatnya pegawai akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan
dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain
karena selalu merasa curiga terhadap pegawai tersebut yang terlihat selalu berbuat
curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang pegawai pernah melakukan kecurangan
ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari
pegawai lainnya. Sebaliknya jika terbukti bahwa pegawai tersebut tidak pernah
melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan maka pegawai ter-sebut tidak
akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Prinsip kejujuran
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 142
harus dapat dipegang teguh oleh setiap pegawai sejak masa-masa ini untuk memupuk
dan membentuk karakter mulia di dalam setiap pribadi pegawai.
2. Kepedulian
Menurut Sugono definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan
menghiraukan (Sugono: 2008). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang pegawai
dalam kehidupan di dunia kerja dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa
depan, seorang pegawai perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik
lingkungan di dalam dunia kerja maupun lingkungan di luar dunia kerja.
Rasa kepedulian seorang pegawai harus mulai ditumbuhkan sejak berada di dunia kerja.
Oleh karena itu upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan pegawai sebagai
subjek kerja sangat penting. Seorang pegawai dituntut untuk peduli terhadap proses
belajar mengajar di dunia kerja, terhadap pengelolalaan sumber daya di dunia kerja
secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam dunia
kerja. pegawai juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar dunia kerja.
Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian di antaranya adalah
dengan menciptakan
Sikap tidak berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang pegawai pernah
melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh
kembali kepercayaan dari pegawai lainnya. Sebaliknya jika terbukti bahwa pegawai
tersebut tidak pernah melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan maka
pegawai tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela
tersebut.
3. Kemandirian
Kondisi mandiri bagi pegawai dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu
dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung
jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana pegawai tersebut harus
mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya
sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan
mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut pegawai
dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan
orang lain (Supardi: 2004).
4. Kedisiplinan
Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan
(Sugono: 2008). Dalam mengatur kehidupan dunia kerja baik kerja maupun sosial
pegawai perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di
barak militier namun hidup disiplin bagi pegawai adalah dapat mengatur dan mengelola
waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas
baik dalam lingkup kerja maupun sosial dunia kerja.
Manfaat dari hidup yang disiplin adalah pegawai dapat mencapai tujuan hidupnya dengan
waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola
suatu kepercayaan. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk
kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan
ketentuan yang berlaku di dunia kerja, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan
fokus pada pekerjaan.
5. Tanggung Jawab
Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan)
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 143
(Sugono: 2008).
Pegawai adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari
penkerjaan terakhirnya yang melanjutkan pekerjaan dalam sebuah lembaga yang
bernama organisasi. Pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki
kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding pegawai yang tidak memiliki
rasa tanggung jawab. pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan
tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat
diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. pegawai
yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan
baik berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari
kepercayaan orang lain terhadap pegawai tersebut. pegawai yang memiliki rasa
tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat
misalkan dalam memimpin suatu kepanitiaan yang diadakan di dunia kerja.
Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah,
baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan
kesadaran akan kewajiban menerina dan menyelesaikan semua masalah yang telah di
lakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan.
6. Kerja keras
Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata ”kemauan” menimbulkan asosiasi
dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian,
pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian
dan pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan pegawai harus berkembang
ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa
menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka
akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu
pegawai dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan dicapai
akan semakin optimum.
Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan
target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya
pengetahuan. Di dalam dunia kerja, para pegawai diperlengkapi dengan berbagai ilmu
pengetahuan.
7. Sederhana
Gaya hidup pegawai merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di
sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak pegawai me-
ngenyam masa penkerjaannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap pegawai
dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat
memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan
semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.
Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, pegawai dibina untuk memprioritaskan
kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter
penting dalam menjalin hubungan antara sesama pegawai karena prinsip ini akan
mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-
sikap negatif lainnya lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari
keinginan yang berlebihan.
8. Keberanian
Jika kita temui di dalam dunia kerja, ada banyak pegawai yang sedang mengalami
kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 144
demi mempertahankan pendirian dan keyakinan pegawai, terutama sekali pegawai harus
mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya.
Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh pegawai dalam kehidupan di dunia kerja dan
di luar dunia kerja. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan
membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain
sebagainya
Prinsip akuntabilitas dapat mulai diterapkan oleh pegawai dalam kehidupan sehari-hari
sebagai pegawai Misalnya program-program kegiatan arus dibuat dengan mengindahkan
aturan yang berlaku di dunia kerja dan dijalankan sesuai dengan aturan.
9. Keadilan
Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.
Bagi pegawai karakter adil ini perlu sekali dibina agar pegawai dapat belajar
mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.
C. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi
Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal
terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi
akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah
faktor eksternal penyebab korupsi.
Ada 5 (lima) prinsip anti korupsi:
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga
mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi
(de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu)
maupun pada level lembaga (Bappenas: 2002). Lembaga-lembaga tersebut berperan
dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor.
Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk
mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban
untuk dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal
(Dubnik: 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk
kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang
diharapkan (Pierre: 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang
yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja
(Prasojo: 2005).
Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah
akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas
outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam
pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui
mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan.
Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang
diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah
kegiatan.
2. Transparansi
Adalah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi
ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan
semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk
penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo: 2007).
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 145
Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses
dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi
mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan
(trust) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang
sangat berharga bagi para pegawai untuk dapat melanjutkan tugas dan
tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan: 2010).
Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu 1) proses penganggaran, 2)
proses penyusunan kegiatan, 3) proses pembahasan, 4) proses pengawasan, dan 5)
proses evaluasi.
Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi,
laporan pertanggung-jawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran.
Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses
pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi
anggaran (anggaran belanja).
Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang
berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan
proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan
pertanggungjawaban secara teknis.
Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan
dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang
diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi.
Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka
dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan
fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.
Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi pegawai untuk dapat melaksanakan
kegiatannya agar lebih baik.
Setelah pembahasan prinsip ini, pegawai sebagai individu dan juga bagian dari
masyarakat/ organisasi/ institusi diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip
transparansi di dalam kehidupan keseharian pegawai.
3. Kewajaran
Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini
ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran,
baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran
ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi,
kejujuran, dan informatif.
Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinam-
bungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off
budget), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai
efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas
dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan.
Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness.
Prinsip kewajaran dapat mulai diterapkan oleh pegawai dalam kehidupan di dunia kerja.
Misalnya, dalam penyusunan anggaran program kegiatan kepegawaian harus dilakukan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 146
secara wajar. Demikian pula dalam menyusun Laporan pertanggung-jawaban, harus
disusun dengan penuh tanggung-jawab.
4. Kebijakan
Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai
prinsip ini ditujukan agar pegawai dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti
korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi
penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini
tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-
undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang
anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui
sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para
pejabat negara.
Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan,
kultur kebijakan. Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung
unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan
tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya.
Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak
kebijakan yaitu keKemenkesan, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga
pemasyarakatan.
Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap,
persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi.
Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat
dalam pemberantasan korupsi.
5. Kontrol Kebijakan
Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya
agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.
Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia,
self-evaluating organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika
pengawasan di Indonesia.
Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan
berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam
penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi.
POKOK BAHASAN 3: UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung
dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Melihat
kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi
perdananya.
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab
korupsi, nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan
korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. dan prinsip-prinsip upaya pemberantasan
korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas
korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang
hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat
untuk memberantas korupsi.
Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk
memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 147
aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut baik ke
Kemenkesan, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga
independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya
dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi.
Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat.
Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut
dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhsuburkan korupsi yang terjadi di Indonesia.
Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal penkerjaan (termasuk Pekerjaan
Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah
demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung
tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat
beragama.
Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga
pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi.
Apa saja yang harus direformasi?
Reformasi ini meliputi reformasi terhadap:
sistem
kelembagaan maupun pejabat publiknya
ruang untuk korupi harus diperkecil
transparansi dan akuntabilitas serta
akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus
ditingkatkan
Pada bagian atau bab ini, akan dipaparkan berbagai upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang dapat dan telah dipraktikkan di berbagai negara. Ada
beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat
upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi.
A. Upaya Pencegahan Korupsi
Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk
memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan the
Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-
Corruption Toolkit (UNODC: 2004).
1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang
independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara di-
dirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman.
Peran lembaga ombudsman--yang kemudian berkembang pula di negara lain-- antara
lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilaku-
kan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu lembaga ini juga mem-berikan
edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta
code of conduct bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan.
Salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta
pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik,
jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC: 2004).
Bagaimana dengan Indonesia?
Kita sudah memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 148
Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan.
Apa saja yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
mencegah dan memberantas korupsi? Adakah yang masih harus diperbaiki dari kinerja
KPK yang merupakan lembaga independen anti-korupsi yang ada di Indonesia? Ada
beberapa negara yang tidak memiliki lembaga khusus yang memiliki kewenangan seperti
KPK Namun tingkat korupsi di negara-negara tersebut sangat rendah. Mengapa?
Salah satu jawabannya adalah lembaga peradilannya telah berfungsi dengan baik dan
aparat penegak hukumnya bekerja dengan penuh integritas.
Bagaimana dengan Indonesia?
Tingkat keKemenkesan, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial (tidak
memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena
kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu
(unable), mungkin masih dapat dimaklumi.
Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan.
Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau (unwilling) atau tidak memiliki
keinginan yang kuat (strong political will) untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat
dalam berbagai perkara korupsi.
Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus
ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali ‘tidak punya gigi’
ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk
mencegah korupsi.
Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak
pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktik
suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara
resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti
mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus ijin usaha atau Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB) dsb.
Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan
memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah
diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan
demikian korupsi besar-besaran umumnya terjadi di Ibukota negara atau di Jakarta.
Dengan otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kantong korupsi tidak
terpusat hanya di ibukota negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu
kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau
diawasi terbukti melakukan korupsi
Selain sistem perekruitan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan
pada pada proses (proccess oriented) dan hasil kerja akhir (result oriented) perlu
dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri,
bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari
atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai
negeri.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 149
2. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk
mendapatkan akses terhadap informasi (access to information). Sebuah sistem harus
dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala
informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup
orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat
kebijakan dan menjalankannya secara transparan.
Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan
yang dibuat dan akan dijalankan.
Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya
korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian.
3. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk
melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun
sesudah menjabat.
Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah
kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah
selesai menjabat.
Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah
maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan
melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau
akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran
tersebut.
Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat
untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini yang sangat penting dari upaya
memberantas korupsi.
Salah satu cara untuk meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan
kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai
apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan.
Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak
maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi.
Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi ‘harus’
dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya
korupsi bahkan memasukkan materi budaya anti korupsi menajdi bagian dari
pembelajaran pada pelatihan bagi aparatur sipil negara.
Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan
memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk
melaporkan kasus korupsi.
Sebuah mekanisme harus dikembangkan dimana masyarakat dapat dengan mudah dan
bertanggung-jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut
harus dipermudah atau disederhanakan misalnya via telepon, surat atau telex.
Di beberapa Negara, pasal mengenai ‘fitnah’ dan “pencemaran nama baik” tidak dapat
diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa
bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 150
Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang
diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Media memiliki
fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingat lokal atau internasional juga
memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah
bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan
begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti-Korupsi banyak
bermunculan. Sama seperti pers yang bebas, LSM memiliki fungsi untuk melakukan
pengawasan atas perilaku pejabat publik.
Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi
sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab
korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau
individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem.
Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau
setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.
Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam
diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran,
kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan
keadilan.
Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor
eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki
nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti
korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam
suatu organisasi/ institusi/ masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan
nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
B. Upaya Pemberantasan Korupsi
Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul
dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi
ibarat penyakit ‘kanker ganas’ yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia
menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini
menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk
diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu,
korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat.
Dalam pemberantasan korupsi sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya
pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat
serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep
atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi.
Upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan
pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang
hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat
untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian?
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 151
Untuk memberantas korupsi tidak dapat hanya mengandalkan hukum (pidana) saja dalam
memberantas korupsi.
Padahal beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang
paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada
pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap
harus dihukum (diberi pidana), namun berbagai upaya lain harus tetap terus
dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya.
Adakah gunanya berbagai macam peraturan perundang-undangan, lembaga serta sistem
yang dibangun untuk menghukum pelaku korupsi bila hasilnya tidak ada?. Jawabannya
adalah: jangan hanya mengandalkan satu cara, satu sarana atau satu strategi saja yakni
dengan menggunakan sarana penal, karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat
bekerja secara efektif. Belum lagi kalau kita lihat bahwa ternyata lembaga serta aparat
yang seharusnya memberantas korupsi justru ikut bermain dan menjadi aktor yang ikut
menumbuhsuburkan praktik korupsi.
C. Strategi Komunikasi Pemberantasan Korupsi (PK)
1. Adanya Regulasi
KEPMENKES No: 232 Menkes/Sk/Vi/2013, Tentang Strategi Komunikasi Pemberantasan
Budaya Anti Korupsi Kementerian Kesehatan Tahun 2013.
Penyusunan dan sosialisasai Buku panduan Penggunaan fasilitas kantor
Penyusunan dan sosialisasi Buku Panduan Memahami Gratifikasi
Workshop/ pertemuan peningkatan pemahaman tentang antikorupsi dengan topik
tentang gaya hidup PNS, kesederhanaan, perencanaan keuangan keluarga sesuai
dengan kemampuan lokus
Penyebarluasan nilai-nilai anti korupsi (disiplin dan tanggung jawab) berkaitan dengan
kebutuhan pribadi dan persepsi gratifikasi
Penyebarluasan informasi tentang peran penting dann manfaat whistle blower dan
justice collaborator
2. Perbaikan Sistem
Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi
perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering
digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum.
Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simpel dan efisien.
Menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi. Reformasi birokrasi.
Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, memberikan
aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan
penggunaannya untuk kepentingan pribadi.
Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara
tegas.
Penerapan prinsip-prinsip Good Governance.
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error.
3. Perbaikan manusianya
KPK terus berusaha melakukan pencegahan korupsi sejak dini. Berdasarkan studi yang
telah dilakukan, ditemukan bahwa ada peran penting keluarga dalam menanamkan nilai
anti korupsi.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ada peran penting keluarga
dalam proses pencegahan korupsi. Keluarga batih menjadi pihak pertama yang bisa
menanamkan nilai anti korupsi saat anak dalam proses pertumbuhan. "Keluarga batih itu
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 152
adalah pihak pertama yang bisa menanamkan nilai anti korupsi ke anak. Seiring anak
tumbuh, nilai anti korupsi itu semakin mantap.
KPK menekankan pencegahan korupsi sejak dini. Sebabnya, ketika seseorang sudah
beranjak dewasa dan memiliki pemahaman sendiri, penanaman nilai anti korupsi akan
susah ditanamkan. Ketika orang sudah dewasa, apalagi dia adalah orang yang pandai
dan cerdas, sangat susah menanamkan nilai anti korupsi karena mereka sudah punya
pemahaman sendiri.
Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman. Mengoptimalkan peran agama
dalam memberantas korupsi. Artinya pemuka agama berusaha mempererat ikatan
emosional antara agama dengan umatnya dan menyatakan dengan tegas bahwa
korupsi adalah perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari
segala bentuk korupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian
masyarakat untuk melawan korupsi.
Memperbaiki moral sebagai suatu bangsa. Pengalihan loyalitas (kesetiaan) dari
keluarga/ klan/ suku kepada bangsa. Menolak korupsi karena secara moral salah
(Klitgaard, 2001). Morele herbewapening, yaitu mempersenjatai/ memberdayakan
kembali moral bangsa (Frans Seda, 2003).
Meningkatkan kesadaran hukum, dengan sosialisasi dan penkerjaan anti korupsi.
Mengentaskan kemiskinan. Meningkatkan kesejahteraan.
Memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, pemimpin yang memiliki
kepedulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan.
Bagaimana cara penanggulangan korupsi?
Cara penanggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan
(preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos
kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau
perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji),
menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan
pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan
pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan
sanksi sosial,dan pendidikan dapat menjadi instrumen penting bila dilakukan dengan tepat
bagi upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya korupsi.
Sementara itu untuk tindakan represif penegakan hukum dan hukuman yang berat perlu
dilaksanakan dan apabila terkait dengan implementasinya maka aspek individu penegak
hukum menjadi dominan, dalam perspektif ini pendidikan juga akan berperan penting di
dalamnya.
POKOK BAHASAN 4: TATA CARA PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
Dalam menjalani aktivitas sehari-hari dilingkup perusahaan mungkin kita melihat ada
beberapa “oknum” pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi namun kita binggung
bagaimana cara melaporkan kasus tersebut..
Pengertian Laporan/ pengaduan dapat kita temukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau
kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah
atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.(Pasal 1 angka 24 KUHAP).
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 153
Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan adalah:
Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah
melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP).
A. Laporan
Dari pengertian di atas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat
yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah
peristiwa pidana/ kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan
pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang
terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau
bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tidak kejahatan memiliki kewajiban untuk
melaporkan tindakan tersebut.
Selanjutnya, di mana kita melapor? Dalam hal jika Anda ingin melaporkan suatu tindak
pidana korupsi yang terjadi di lingkungan kementerian Kesehatan, saat ini kementerian
Kesehatan melalui Inspektorat jenderal sudah mempunyai mekanisme pengaduan tindak
pidana korupsi.
Mekanisme Pelaporan
1. Tim Dumasdu pada unit Eselon 1 setiap bulan menyampaikan laporan penanganan
pengaduan masyarakat dalam bentuk surat kepada Sekretariat Tim Dumasdu.
Laporan tersebut minimal memuat informasi tentang nomor dan tanggal pengaduan, isi
ringkas pengaduan, posisi penanganan dan hasilnya penanganan.
2. Sekretariat Tim Dumasdu menyusun laporan triwulanan dan semesteran untuk
disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dan pihak-pihak terkait lainnya.
B. Pengaduan
Pengaduan yang dapat bersumber dari berbagai pihak dengan berbagai jenis
pengaduan, perlu diproses ke dalam suatu sistem yang memungkinkan adanya
penanganan dan solusi terbaik dan dapat memuaskan keinginan publik terhadap
akuntabilitas pemerintahan.Ruang lingkup materi dalam pengaduan adalah adanya
kepastian telah terjadi sebuah tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan, dimana
tindakan seorang pengadu yang mengadukan permasalahan pidana delik aduan harus
segera ditindak lanjuti dengan sebuah tindakan hukum berupa serangkaian tindakan
penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya dalam proses
penerimaan pengaduan dari masyarakat, seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini
internal di Kementerian Kesehatan khususnya Inspektorat Jenderal, harus bisa
menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh seorang pengadu merupakan
sebuah tindak pidana delik aduan ataukah bukan.
Penyelesaian Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Tim Dumasdu secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi (money)
terhadap hasil ADTT/Investigasi, berkoordinasi dengan Bagian Analisis Pelaporan dan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (APTLHP). Pelaksanaan money dan penyusunan
laporan hasil money dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
berlaku pada Inspektorat Jenderal.
Penyelesaian hasil penanganan dumas agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:
1. Tindakan administratif;
2. Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
3. Tindakan perbuatan pidana;
4. Tindakan pidana;
5. Perbaikan manajemen.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 154
C. Tata Cara Penyampaian Pengaduan
Prosedur Penerimaan Laporan kepada Kemenkes adalah Berdasarkan Permenkes
Nomor 49 tahun 2012 tentang Pengaduan kasus korupsi, beberapa hal penting yang
perlu diketahui antaranya.
Pengaduan masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan dikelompokkan dalam:
1. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; dan
2. Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan adalah: mengandung informasi atau
adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh aparatur Kementerian Kesehatan sehingga mengakibatkan kerugian
masyarakat atau negara.
Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan merupakan pengaduan masyarakat
yang isinya mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan
lain sebagainya, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan masyarakat. Masyarakat terdiri atas orang perorangan, organisasi
masyarakat, partai politik, institusi, kementerian/lembaga pemerintah, dan pemerintah
daerah.
Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat disampaikan secara
langsung melalui tatap muka, atau secara tertulis/surat, media elektronik, dan media
cetak kepada pimpinan atau pejabat Kerrienterian Kesehatan. Pengaduan masyarakat
berkadar pengawasan dapat disampaikan secara langsung oleh masyarakat kepada
Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Pengaduan masyarakat tidak
berkadar pengawasan dapat disampaikan secara langsung oleh masyarakat kepada
sekretariat unit utama dilingkungan Kementerian Kesehatan.Pengaduan masyarakat di
lingkungan Kementerian Kesehatan harus ditanggapi dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kemenkes
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/ VIII/ 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Kesehatan, sehingga dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut perlu suatu pedoman
penanganan pengaduan masyarakat yang juga merupakan bentuk pengawasan. Selain
itu untuk penanganan pengaduan masyarakat secara terkoordinasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan telah dibentuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/
Menkes/ SK/ III/ 2012 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di
Lingkungan Kementerian Kesehatan (Tim Dumasdu) yang anggotanya para Kepala
bagian Hukormas yang ada pada masing-masing Unit Eselon I di Kementerian
Kesehatan.
Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan ditangani oleh Tim
Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan
yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan kewenangan masing-masing. Penanganan
pengaduan masyarakat terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan harus dilakukan
secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan Penanganan pengaduan
masyarakat meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan lebih lanjut, pelaporan, dan
pengarsipan.
Penanganan lebih lanjut berupa tanggapan secara langsung melalui klarifikasi atau
memberi jawaban, dan penyaluran/ penerusan kepada unit terkait yang
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 155
berwenang menangani. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan
masyarakat tercantum dalam Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di
Lingkungan Kementerian Kesehatan
Pencatatan Pengaduan
Pada dasarnya pengaduan disampaikan secara tertulis. Walaupun peraturan yang ada
menyebutkan bahwa pengaduan dapat dilakukan secara lisan, tetapi untuk lebih
meningkatkan efektifitas tindak lanjut atas suatu perkara, maka pengaduan yang diterima
masyarakat hanya berupa pengaduan tertulis.
Pencatatan pengaduan masyarakat oleh Tim Dumasdu dilakukan sebagai berikut:
1. Pengaduan masyarakat (dumas) yang diterima oleh Tim Dumasdu pada Unit Eselon I
berasal dari organisasi masyarakat, partai politik, perorangan atau penerusan
pengaduan oleh Kementerian/ Lembaga/ Komisi Negara dalam bentuk surat, fax, atau
email, dicatat dalam agenda surat masuk secara manual atau menggunakan aplikasi
sesuai dengan prosedur pengadministrasian/ tata persuratan yang berlaku. Pengaduan
yang disampaikan secara lisan agar dituangkan ke dalam formulir yang disediakan.
2. Pencatatan dumas tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi tentang nomor dan
tanggal surat pengaduan, tanggal diterima, identitas pengadu, identitas terlapor, dan inti
pengaduan.
3. Pengaduan yang alamatnya jelas, segera dijawab secara tertulis dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pengaduan diterima, dengan tembusan
disampaikan kepada Sekretariat Tim Dumasdu pada Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan.
POKOK BAHASAN 5: GRATIFIKASI
A. Pengertian Grafitasi
Bagi sebagian orang mungkin sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kata
Gratifikasi. Tapi Saya lebih senang menafsirkan kata tersebut dengan kata yang
mendefinisikan sesuatu yang berarti “gratis di kasih”. Gratifikasi menurut kamus hukum
berasal dari Bahasa Belanda, “Gratificatie”, atau Bahasa Inggrisnya “Gratification“ yang
diartikan hadiah uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,1998) Gratifikasi
diartikan pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.
Menurut UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah Pemberian
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Ada beberapa contoh penerimaan gratifikasi, diantaranya yakni:
Seorang pejabat negara menerima “uang terima kasih” dari pemenang lelang;
Suami/ Istri/ anak pejabat memperoleh voucher belanja dan tiket tamasya ke luar
negeri dari mitra bisnis istrinya/ suaminya;
Seorang pejabat yang baru diangkat memperoleh mobil sebagai tanda perkenalan dari
pelaku usaha di wilayahnya;
Seorang petugas perijinan memperoleh uang “terima kasih” dari pemohon ijin yang
sudah dilayani.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 156
Pemberian bantuan fasilitas kepada pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif tertentu,
seperti: Bantuan Perjalanan + penginapan, Honor-honor yang tinggi kepada pejabat-
pejabat walaupun dituangkan dalam SK yang resmi), Memberikan fasilitas Olah Raga
(misal, Golf, dll); Memberikan hadiah pada event-event tertentu (misal, bingkisan hari
raya, pernikahan, khitanan, dll).
Pemberian gratifikasi tersebut umumnya banyak memanfaatkan momen-momen ataupun
peristawa-peristiwa yang cukup baik, seperti: Pada hari-hari besar keagamaan (hadiah
hari raya tertentu), hadiah perkawinan, hari ulang tahun, keuntungan bisnis, dan
pengaruh jabatan
Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pengecualian Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1):
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima
melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
B. Aspek Hukum
Aspek hukum gratifikasi meliputi tiga unsur yaitu: (1) dasar hukum, (2) subyek hukum, (3)
Obyek Hukum. Ada dua Dasar Hukum dalam gratifikasi yaitu: (1) Undang-undang Nomor
30 Tahun 2002 dan (2) Undang2-undang No 20 Tahun 2001.
Menurut undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi pasal 16: “ setiap PNS atau Penyelenggara Negara yang menerima
gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK”. Undang-undang nomor 20 tahun 2001,
menurut UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi pasal 12 C Ayat (1)
tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Ayat 2
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh
penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut
diterima.
Subyek hukum terdiri dari: (1) penyelenggara negara, dan (2) pegawai negeri.
Penyelenggara negara meliputi: pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabata
negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat lain yang memiliki
fungsi startegis dalam kaitannya dalam penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil meliputi pegawai negeri spil
sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepegawaian, pegawai negeri spil
sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, orang yang
menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji
atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau
daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas negara atau rakyat
Obyek Hukum gratifikasi meliputi: (1) uang (2) barang dan (3) fasilitas
C. Gratifikasi Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Korupsi
Gratifikasi dikatakan sebagai pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannnya dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 157
Suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana
suap khsuusnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada
saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima
suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian
tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.
Bentuknya:
Pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, dalam bentuk
barang, uang, fasilitas
D. Contoh Gratifikasi
Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain:
Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan
anaknya;
Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/ pegawai negeri atau keluarganya untuk
keperluan pribadi secara cuma-cuma;
Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/ pegawai negeri untuk pembelian
barang atau jasa dari rekanan;
Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan
kerja;
Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya
keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
Berdasarkan contoh diatas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi
adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau
kedinasan dan/ atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan
pejabat/ pegawai negeri dengan sipemberi.
E. Sanksi Gratifikasi
Sanksi pidana yang menerima gratifikasi dapat dijatuhkan bagi pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang:
1. menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau
janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji
tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
2. menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau
janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,
seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum
tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan
merupakan utang;
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 158
6. pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan
barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal
tersebut bukan merupakan utang;
7. pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya
terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah
merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut
bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
8. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan,
untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
POKOK BAHASAN 6: KASUS-KASUS KORUPSI
Dari banyaknya proyek di Kemenkes, ada beberapa yang disorot aparat penegak
hukum karena diduga sarat dengan praktik korupsi. Mulai dari kasus korupsi pengadaan
alat kesehatan untuk penanggulangan flu burung tahun kemudian bertambah dengan
kasus pengadaan alat kesehatan untuk pusat penanggulangan krisis di Kementerian
Kesehatan, kasus pengadaan alat rontgen portable dan kasus pengadaan alat bantu
belajar mengajar pendidikan dokter. Mengapa hal tersebut terjadi adalah akibat
kesalahan prosedur dalam pengadaan barang dengan menggunakan metoda
penunjukkan langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Kasus lainnya yang juga terjadi di lingkungan Kementerian Kesehatan khususnya tahun
2010 ke bawah adalah kasus perjalanann dinas (perjadin). Banyak kecurangan yang
dilakukan pada kegiatan perjadin, pengurangan jumlah hari, ketidaksesuaian antara
pertanggungjawaban perjadin dengan riil yang dikeluarkan, hingga perjadin fiktif.
Kegiatan lainnya yang juga menjadi perhatian adalah paket meeting dan pelatihan
berupa pengurangan jumlah hari, pengurangan jumlah orang, volume pertemuan. Hal
lainnya yang juga sangat penting adalah tidak sesuainya antara kegiatan yang diusulkan
dengan rencana program yang sudah disusun selama lima tahun. Pada modul ini akan
dibahas secara detail tentang kasus pengadaan barang dan jasa yang merupakan kasus
terbanyak.
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintahan merupakan salah satu sektor yang
rentan penyimpangan,Kasus yang ditangani KPK, 60 persen sampai 70 persennya
terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi, pengadaan barang dan jasa memang
rawan terjadinya korupsi. salah satunya dalam bentuk tindak pidana korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Salah satu faktor penyebab memungkinkan terjadinya penyimpangan, masih lemahnya
sistem pengawasan yang dilakukan terhadap keseluruhan tahap dan proses PBJ
tersebut, sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.
Upaya pembenahan sistem PBJ sudah dilakukan dimulai dari aspek normatif/ regulasi
maupun teknis. Namun tentu saja perbaikan sistem tersebut tidak dibarengi dengan
perbaikan pada aspek pengawasan. Ini tentu saja menjadi kerugian bagi masyarakat
sebagai penerima hasil proses PBJ.
Sistem pengawasan yang ada, baik di tingkat pusat (Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah/ LKPBJP), maupun yang ada diinternal pemerintah belum
sepenuhnya berfungsi dengan baik. Sehingga sangat dimungkinkan terjadinya
penyimpangan. Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia,
masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya
korupsi. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana
diatur dalam Kepres maupun Perpres, masih memungkinkan Panitia Pengadaan dan
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 159
Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan korupsi di setiap tahapannya. Kelemahan
tersebut terbukti dengan begitu besarnya kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan
barang dan jasa pemerintah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laporan tahunan KPK hingga tahun 2012, kasus korupsi di sektor PBJ menjadi
kasus terbesar yang ditangani KPK tidak hanya di Kemenkes saja namun di beberapa
kementerian dan di daerah.
Beberapa hal yang sering terjadi di antaranya:
1. kegiatan pengadaan sering tidak tepat sasaran
2. Kemahalan harga versus kewajaran harga
3. Kekurangan kuantitas (volume kegiatan) program versus volume kegiatan fisik
4. Kekurangan kualitas
Rangkuman
Korupsi, apakah sudah jadi budaya atau bukan, Korupsi adalah penyalahgunaan
wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan
teman atau kelompoknya, baik dalam bentuk Bribery, extortion, maupun nepotism.
Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-
sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa.
Cara penanggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan
(preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos
kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau
perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji),
menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan
pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam
memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya
kontrol sosial dan sanksi sosial,dan pendidikan dapat menjadi instrumen penting bila
dilakukan dengan tepat bagi upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya korupsi.
Sementara itu untuk tindakan represif penegakan hukum dan hukuman yang berat perlu
dilaksanakan dan apabila terkait dengan implementasinya maka aspek individu penegak
hukum menjadi dominan, dalam perspektif ini pendidikan juga akan berperan penting di
dalamnya.
Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis pegawai
Setidaknya, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi ini. Pertama,
Untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap pegawai. Melalui pendidikan ini,
diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap pegawai dan
tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga pekerjaan membangun bangsa yang
terseok-seok karena adanya korupsi di masa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi
sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. Kedua,
Menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga
penegak hukum seperti KPK, KeKemenkesan dan Kejaksaan agung, melainkan
tanggung jawab setiap anak bangsa.
Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk
mendapatkan akses terhadap informasi (access to information). Sebuah sistem harus
dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala
informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup
orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat
kebijakan dan menjalankannya secara transparan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 160
Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan
dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat
mapun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya.
VIII. REFERENSI
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013
Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008
Permenpan Nomor 5 tahun 2009
Permenkes No 49 tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Permenkes nomor 134 tahun 2012 tentang Tim Pengaduan Masyarakat
Permenkes Nomor 14 tahun 2014 Kebijakan tentang Gratifikasi bidang Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 232/ Menkes/ SK/ VI/ 2013 Tentang
Strategi Komunikasi Penkerjaan dan Budaya Anti Korupsi
Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd Budaya Korupsi dan Pendidikan Tantangan bagi
Dunia Pendidikan
KPK, Buku Saku Gratifikasi
IX. LAMPIRAN (Terlampir)
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 161
MODUL PENUNJANG 3
RENCANA TINDAK LANJUT
I. DESKRIPSI SINGKAT
Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan suatu dokumen tentang rencana yang
akan dilakukan setelah mengikuti suatu kegiatan atau merupakan tindak lanjut dari
kegiatan tersebut. Dalam suatu pelatihan, RTL merupakan dokumen rencana yang
memuat tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan setelah peserta kembali
ketempat tugas untuk menerapkan hasil pelatihan.
Modul RTL ini disusun dalam rangka untuk membekali para fasilitator STBM-stunting
agar mampu memahami rincian kegiatan dan dapat menyusun RTL yang akan
dilaksanakan di tempat tugasnya masing-masing.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menyusun rencana tindak lanjut
pelaksanaan kegiatan STBM-stunting di wilayah kerjanya masing-masing.
B. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti materi ini peserta mampu:
1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup RTL,
2. Menjelaskan langkah-langkah penyusunan RTL,
3. Menyusun RTL dan Gantt Chart untuk kegiatan yang akan dilakukan,
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan STBM-stunting.
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai
berikut:
A. Pokok Bahasan 1 : RTL
1. Pengertian
2. Ruang Lingkup
B. Pokok Bahasan 2 : Langkah-langkah penyusunan RTL
C. Pokok Bahasan 3 : Penyusunan RTL dan bagan Gantt (Gantt Chart)
D. Pokok Bahasan 4 : Evaluasi pelaksanaan STBM-Stunting
IV. METODE
Ceramah tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan.
V. MEDIA DAN ALAT BANTU
Bahan tayang, LCD proyektor, computer, flipchart, spidol, meta plan, kain tempel,
lembar/format RTL.
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini sebanyak 3 jam pelajaran (T: 1 jp; P: 2
jp; PL: 0) @ 45 menit untuk memudahkan proses pembelajaran, dilakukan langkah-
langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
Langkah 1 : Pengkondisian (15 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Memperkenalkan diri,
b. Menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus,
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 162
c. Menggali pendapat peserta tentang pengertian dan ruang lingkup dan
langkah-langkah RTL,
d. Berdasarkan pendapat peserta, fasilitator menjelaskan pentingnya RTL,
e. Memberi kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang
kurang jelas dan fasilitator menjawab pertanyaan peserta tersebut.
2. Kegiatan Peserta
a. Mempersiapkan diri dan alat tulis bila diperlukan.
b. Mengemukakan pendapat atas pertanyaan fasilitator.
Langkah 2. Pembahasan per materi (120 menit)
A. Menyusun RTL (60 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Membagi kelompok berdasarkan termpat kerjanya
b. Memberikan format RTL
2. Kegiatan Peserta
a. Melakukan diskusi kelompok dan menyusun RTL
B. Mempresentasikan RTL (45 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. memilih wakil kelompok untuk menyajikan RTLnya, diupayakan seluruh
kelompok mendapatkan kesempatan untuk menyajikan RTLnya secara
bergantian
b. memberi kesempatan kepada peserta lainnya untuk menanggapi
penyajian RTL yang disajikan
c. menyampaikan simpulani tentang RTL yang telah disusun peserta.
2. Kegiatan Peserta
a. Mempresentasikan RTL yang telah disusun.
Langkah 3. Kesimpulan (15 menit)
1. Kegiatan Fasilitator
a. Menutup sesi pembelajaran dengan memastikan TPU dan TPK sesi telah
tercapai.
b. Memberikan apresiasi pada peserta.
c. Kegiatan Peserta
2. Kegiatan Peserta
c. Mengajukan pertanyaan atau komentar yang diminta Fasilitator.
d. Menjawab salam.
VII. URAIAN MATERI
POKOK BAHASAN 1 : RENCANA TINDAK LANJUT
Proses diklat merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan.
Kegiatan tersebut dimulai dengan Analisis Kebutuhan Pelatihan, Penentuan Tujuan
Pelatihan, Rancang Bangun Program Pelatihan, Pelaksanaan Pelatihan serta Evaluasi
Pelatihan. Oleh karena itu seorang pengelola (fasilitator) pelatihan dituntut memiliki
kompetensi dalam bidang tersebut. Disamping itu pengelola pelatihan dituntut selalu
mengembangkan organisasinya agar mencapai visi dan misi organisasi secara optimal.
Untuk itu maka wawasan dan pengetahuan serta ketrampilan dalam bidang membuat
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 163
perencanaan tindak lanjut perlu mendapat prioritas. Hal ini dimaksudkan agar peserta
memahami dengan jelas arah dan tujuan pelatihan yang telah dijalaninya.
a. Pengertian Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut (RTL) merupakan suatu dokumen yang menjelaskan tentang
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, setibanya peserta di wilayah kerja masing-
masing dengan memperhitungkan hal-hal yang telah ditetapkan berdasarkan potensi dan
sumber daya yang ada.
RTL merupakan sebuah rencana kerja yang dibuat secara individual oleh peserta diklat
yang berisi tentang rencana kerja yang menjadi tugas dan wewenangnya. Rencana ini
dibuat setelah peserta pelatihan mengikuti seluruh mata diklat yang telah diberikan.
b. Ruang Lingkup Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Penyusunan Rencana Tindak Lanjut ini dimaksudkan untuk mengaplikasikan teori-teori
yang telah diberikan dalam pelatihan ini dengan pengalaman peserta latih. Perpaduan
antara teori dan pengalaman ini merupakan salah satu metode untuk lebih
meningkatkan tingkat pemahaman peserta diklat akan teori-teori yang telah diberikan
selama pelatihan, sehingga tujuan pembelajaran khusus akan tercapai secara maksimal
Rencana tindak lanjut sangat diperlukan bagi Peserta pelatihan, Widyaiswara dan
penyelenggara Diklat. Hal ini disebabkan Rencana Tindak Lanjut merupakan sebuah
rencana kerja yang dibuat oleh individual yang berisi tentang rencana unit organisasi
diklat yang menjadi tugas dan wewenangnya.
Didalam membuat rencana tindak lanjut perlu mengacu pada struktur / sistematika
rencana tindak lanjut tertentu seperti yang telah disepakati dalam proses pembelajaran.
Oleh karena itu RTL memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Terarah
Setiap kegiatan yang dicantumkan dalam RTL hendaknya terarah untuk mencapai
tujuan.
2. Jelas
Isi rencana mudah dimengerti dan ada pembagian tugas yang jelas antara orang-
orang yang terlibat didalam masing-masing kegiatan.
3. Fleksibel
Mudah disesuaikan dengan perkembangan situasi. Oleh karena itu RTL mempunyai
kurun waktu relatif singkat.
Tujuan RTL adalah agar peserta latih / institusi memiliki acuan dalam menindak lanjuti
suatu kegiatan pelatihan.
Ruang lingkup Rencana Tindak lanjut (RTL) sebaiknya minimal :
1. Menetapkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan,
2. Menetapkan tujuan setiap kegiatan yang ingin dicapai,
3. Menetapkan sasaran dari setiap kegiatan,
4. Menetapkan metode yang akan digunakan pada setiap kegiatan,
5. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan
6. Menetapkan siapa pelaksana atau penanggung jawab dari setiap kegiatan,
7. Menetapkan besar biaya dan sumbernya.
POKOK BAHASAN 2. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RTL.
Berdasarkan hasil analisis kemudian disusun RTL dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Identifikasi dan buat perumusan yang jelas dari semua kegiatan yang akan
dilaksanakan (apa/what). Pada saat menentukan kegiatan hendaknya
mereview modul Pelatihan Fasilitator STBM.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 164
2. Tentukan apa tujuan dari masing-masing kegiatan yang telah ditentukan.
3. Tentukan sasaran dari masing-masing kegiatan yang telah ditentukan.
4. Tetapkan cara atau metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan setiap
kegiatan (bagaimana/how).
5. Perkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan (kapan/when), dan
tentukan lokasi yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan
(tempat/where).
6. Perkirakan besar dan sumber biaya yang diperlukan pada setiap kegiatan.
(How much)
7. Tetapkan siapa mengerjakan apa pada setiap kegiatan dan bertanggung
jawab kepada siapa (siapa/who).
Oleh karena itu dalam menyusun RTL harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
1. Kegiatan
yaitu uraian kegiatan yang akan dilakukan, didapat melalui identifikasi kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar hal ini terealisasi maka
di identifikasi kegiatan kegiatan apa yang diperlukan.
2. Tujuan
adalah membuat ketetapan ketetapan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang
direncanakan pada unsur nomor 1. Penetapan tujuan yang baik adalah di rumuskan
secara konkrit dan terukur.
3. Sasaran
yaitu seseorang atau kelompok tertentu yang menjadi target kegiatan yang
direncanakan.
4. Cara/Metode
yaitu cara yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan agar tujuan yang telah
ditentukan dapat tercapai.
5. Waktu dan Tempat
Dalam penentuan waktu sebaiknya menunjukkan kapan suatu kegiatan dimulai
sampai kapan berakhir. Apabila dimungkinkan sudah dilengkapi dengan tanggal
pelaksanaan. Hal ini untuk mempermudah dalam persiapan kegiatan yang akan
dilaksanakan, serta dalam melakukan evaluasi. Sedangkan dalam menetapkan
tempat, seyogyanya menunjukkan lokasi atau alamat kegiatan akan dilaksanakan
6. Biaya
Agar RTL dapat dilaksanakan perlu direncanakan anggaran yang dibutuhkan untuk
kegiatan tersebut.Akan tetapi perencanaan anggaran harus realistis untuk kegiatan
yang benar-benar membutuhkan dana, artinya tidak mengada-ada.
Perhatikan/pertimbangkan juga kegiatan yang memerlukan dana tetapi dapat digabung
pelaksanaannya dengan kegiatan lain yang dananya telah tersedia. Rencana anggaran
adalah uraian tentang biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari
awal sampai selesai.
7. Pelaksana / penanggung jawab
yaitu personal / tim yang akan melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Hal ini
penting karena personal/tim yang terlibat dalam kegiatan tersebut mengetahui dan
melaksanakan kewajiban.
8. Indikator Keberhasilan
merupakan bentuk kegiatan/sesuatu yang menjadi tolok ukur dari keberhasilan dari
pelaksanaan kegiatan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 165
POKOK BAHASAN 3 : PENYUSUNAN RTL DAN GANTT CHART UNTUK KEGIATAN
YANG AKAN DILAKUKAN
a. Penyusunan RTL
Dalam menyusun RTL dapat menggunakan format isian sebagai berikut:
Format Isian Rencana Tindak Lanjut
PELAKSANA/
N CARA/ WAKTU & INDIKATOR
KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA PENANGGUN
O METODE TEMPAT KEBERHASILAN
G JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ds
t
Penjelasan cara pengizian :
Kolom 1 : Kolom nomor
Pada kolom ini dicantumkan nomor kegiatan secara berurutan, mulai dari nomor 1, 2,
3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kegiatan yang direncanakan bedasarkan
hasil identifikasi kegiatan.
Kolom 2 : Kolom kegiatan
Pada kolom ini dicantumkan rincian kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari
persiapan, sampai seluruh pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan selesai.
Kolom 3 : Kolom tujuan
Pada kolom ini dicantumkan tujuan dari setiap kegiatan, yaitu hasil yang ingin dicapai
dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.
Kolom 4 : Kolom sasaran
Pada kolom ini diisi dengan apa/ siapa yang menjadi sasaran atau target dari setiap
kegiatan, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Kolom 5 : Kolom cara/ metode
Pada kolom ini dicantumkan cara-cara/ metode/ teknik pelaksanaan setiap kegiatan.
Kolom 6 : Kolom waktu dan tempat
Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, tahun serta jam pelaksanaan kegiatan, kapan
dimulai dan sampai kapan berakhir, serta dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.
Kolom 7 : Kolom pelaksana/ penanggungjawab
Kolom ini diisi dengan nama pelaksana atau anggota tim yang ditugaskan
melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 166
Kolom 8 : Kolom indikator keberhasilan
Kolom ini mencantumkan tentang apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
b. Gantt Chart
Gantt chart adalah suatu alat yang bernilai khususnya untuk kegiatan-kegiatan
dengan jumlah anggota tim yang sedikit, kegiatan yang mendekati penyelesaian dan
beberapa kendala kegiatan.
Karakteristik Gantt Chart
Gantt chart secara luas dikenal sebagai alat fundamental dan mudah diterapkan oleh
para manajer kegiatan untuk memungkinkan seseorang melihat dengan mudah
waktu dimulai dan selesainya tugas-tugas dan sub- sub tugas dari suatu kegiatan.
Semakin banyak tugas-tugas dalam kegiatan dan semakin penting urutan antara
tugas-tugas maka semakin besar kecenderungan dan keinginan untuk memodifikasi
gantt chart.
Gantt chart membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan “what if” saat melihat
kesempatan-kesempatan untuk membuat perubahan terlebih dahulu terhadap
kebutuhan.
Keuntungan menggunakan Gantt chart :
a. Sederhana, mudah dibuat dan dipahami, sehingga sangat bermanfaat sebagai
alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek.
b. Dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan
sesungguhnya pada saat pelaporan
c. Bila digabungkan dengan metoda lain dapat dipakai pada saat pelaporan.
Kelemahan Gantt Chart :
a. Tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu
kegiatan dan kegiatan yang lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang
diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan
kegiatan.
b. Sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan/pembaharuan bila diperlukan,
karena pada umumnya ini berarti membuat bagan balok baru.
POKOK BAHASAN 4 : EVALUASI PELAKSANAAN STBM-STUNTING
Pelaksanaan kegiatan STBM-stunting oleh para pelaksana STBM-stunting harus
dilakukan evaluasi untuk melihat seberapa jauh kegiatan tersebut memiliki dampak yang
berarti bagi kesehatan masyarakat khususnya dibidang sanitasi.
Pelaksanaan evaluasi kegiatan STBM-stunting perlu dilakukan dalam waktu 6 bulan
sekali untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 167
VIII. REFERENSI
Kemenkes RI, Pusdiklat Aparatur, Rencana Tindak Lanjut, Kurmod Surveillance,
Jakarta: 2008.
BPPSDM Kesehatan, Rencana Tindak Lanjut, Modul TOT NAPZA, Jakarta: 2009.
Kemenkes RI, Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif,
Jakarta: 2010,
Kemenkes RI, Second Decentralized Health Services Project, Model Pelatihan
Pemberdayaan Masyarakat Bagi Petugas Puskesmas, Jakarta: 2010.
IX. LAMPIRAN (Terlampir)
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 168
TIM PENYUSUN
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Direktorat Kesehatan Lingkungan
1. Nugroho Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
2. Yulita Suprihatin
3. Indah Hidayat Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
4. Widya Utami
5. Adelina Hutahuruk
6. Agustina Ruth Sekretariat STBM
Direktorat Gizi Masyarakat
1. Yuni Zahraini Subdit
2. Evarini Ruslina
3. Yvonne Kusumaningtyas
4. Elisa
Sesditjen
1. Rinda Juwita
Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. Masnapita Tambunan Pusat Pelatihan
2. Etna Saraswati Bapelkes Ciloto
3. Zaini Dahlan Pusat Pendidikan
4. Hendro Saputro Pusat Pendidikan
5. Muryoto, SKM, M.Kes Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
6. Nur Hilal, SKM, M.Kes Poltekkes Semarang-Purwokerto
7. Trina Astuti Poltekkes Jakarta II
Asosiasi
1. Alam Harahap HAKLI
2. Titoes Priyo AIP-VOGI
3. Edith Sumedi PERSAGI
Mitra Pembangunan
1. Rahmi Kasri World Bank
2. Nyoman Oka World Bank
3. Elvi Martini World Bank
4. Hening Darpinto MCA-I
5. Rosnani Pangaribuan MCA-I
6. Rostia MCA-I
7. Ronie Prasetyo MCA-I
8. Ismail Waji MCA-I
Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting Halaman 169
Anda mungkin juga menyukai
- TOR tUMBANGDokumen4 halamanTOR tUMBANGDyah FebriyantiBelum ada peringkat
- Naskah Sumpah Profesi Sanitarian SahidDokumen2 halamanNaskah Sumpah Profesi Sanitarian SahidAdithyar Rachman100% (1)
- PHBS SekolahDokumen17 halamanPHBS SekolahUrip Kudu SabarBelum ada peringkat
- Kak MMDDokumen2 halamanKak MMDRuli Tea House100% (1)
- Instrumen Kaji BandingDokumen3 halamanInstrumen Kaji BandingDhina HartikaBelum ada peringkat
- Talkshow Kesehatan AnakDokumen4 halamanTalkshow Kesehatan AnakgeminastitiBelum ada peringkat
- Term of Reference Phbs-Rumah TanggaDokumen7 halamanTerm of Reference Phbs-Rumah TanggaTri Rahmawati RidwanBelum ada peringkat
- Kerangka Acuan Kegiatan Puskesmas KelilingDokumen3 halamanKerangka Acuan Kegiatan Puskesmas KelilingSusila NingsihBelum ada peringkat
- Materi Orientasi Promkes Bagi Kader 2018Dokumen26 halamanMateri Orientasi Promkes Bagi Kader 2018mariaty sinaga100% (1)
- Desa Siaga Pokja KiaDokumen38 halamanDesa Siaga Pokja Kiaradityo utomo100% (2)
- MAKALAH - KamasutraDokumen19 halamanMAKALAH - KamasutraLalu Alan Dzikrul HaqqiBelum ada peringkat
- Kemandirian PosyanduDokumen11 halamanKemandirian Posyandupromkes jembranaBelum ada peringkat
- Lintas SektorDokumen9 halamanLintas SektorUptd Puskesmas Klungkung IBelum ada peringkat
- Files59893buku Saku Tahap Pemberdayaan Masyarakat Bidang KeshatanDokumen28 halamanFiles59893buku Saku Tahap Pemberdayaan Masyarakat Bidang Keshatanhyun .eBelum ada peringkat
- Pemberdayaan MasyarakatDokumen25 halamanPemberdayaan MasyarakatCitra RcDjeppuBelum ada peringkat
- Phbs Tatanan Sekolah 2010Dokumen11 halamanPhbs Tatanan Sekolah 2010niaasetaBelum ada peringkat
- Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Di Kecamatan Lemito, Kabupaten PohuwatoDokumen41 halamanLaporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Di Kecamatan Lemito, Kabupaten PohuwatoFitrop Meylinda100% (1)
- EvaluasiDokumen237 halamanEvaluasiecha_anthropologyBelum ada peringkat
- Contoh Kak GermasDokumen4 halamanContoh Kak Germasemy nurwati100% (1)
- Posyandu Model MultifungsiDokumen38 halamanPosyandu Model MultifungsiYeppiBelum ada peringkat
- UAS HERU S G LUTANG Kebijakan Dan Manajemen KesehatanDokumen28 halamanUAS HERU S G LUTANG Kebijakan Dan Manajemen KesehatanKing YoutubeBelum ada peringkat
- Kerangka Acuan Penyuluhan Kelompok 2019 IniDokumen4 halamanKerangka Acuan Penyuluhan Kelompok 2019 IniPROMKESBelum ada peringkat
- Bukti Bukti Inovasi Upaya Kesehatan MasyarakatDokumen6 halamanBukti Bukti Inovasi Upaya Kesehatan MasyarakatAnonymous 1sVrlmIoCABelum ada peringkat
- HimbauanDokumen37 halamanHimbauanRiza sari putriBelum ada peringkat
- Blangko Format Laporan Bulanan Promkes 2021Dokumen36 halamanBlangko Format Laporan Bulanan Promkes 2021SisinfoDPD PPNI PurwakartaBelum ada peringkat
- SOP Penyuluhan Kelompok Di Luar GedungDokumen2 halamanSOP Penyuluhan Kelompok Di Luar GedungIntan AyuBelum ada peringkat
- Isi Pedoman Kesrak 2017Dokumen66 halamanIsi Pedoman Kesrak 2017yoryma75% (4)
- Tor Pembinaan Germas DealDokumen3 halamanTor Pembinaan Germas DealYenthi LugaBelum ada peringkat
- Poa Sa Ukm KDW-1Dokumen26 halamanPoa Sa Ukm KDW-1inaBelum ada peringkat
- Instrumen Monitoring Promosi KesehatanDokumen25 halamanInstrumen Monitoring Promosi KesehatanIndah Bibah100% (1)
- Panduan GermasDokumen48 halamanPanduan GermasKOMSOS PAROKI SANTO GREGORIUS AGUNG JAMBIBelum ada peringkat
- 5.1.6.2 Kak Pemberdayaan MasyarakatDokumen5 halaman5.1.6.2 Kak Pemberdayaan MasyarakatwennyrslnaBelum ada peringkat
- Sop Pembinaan SBHDokumen3 halamanSop Pembinaan SBHumi indah warnaningsihBelum ada peringkat
- Analisis Situasi Pasar Combi Dilo Dan MiloDokumen10 halamanAnalisis Situasi Pasar Combi Dilo Dan MiloRizki FajariyahBelum ada peringkat
- POSYANDUDokumen52 halamanPOSYANDUbelajarterusmenerus100% (3)
- Sop MMD Revisi 2Dokumen3 halamanSop MMD Revisi 2Puskesmas BanjarBelum ada peringkat
- Notulen FKKDokumen4 halamanNotulen FKKtri kustiwiBelum ada peringkat
- Lampiran 3 SAP Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada BalitaDokumen7 halamanLampiran 3 SAP Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada BalitaArna HarnaBelum ada peringkat
- Banyuwangi - Faskes BpjsDokumen45 halamanBanyuwangi - Faskes BpjsAiu DiiBelum ada peringkat
- Materi Penyuluhan KBDokumen14 halamanMateri Penyuluhan KBRisnaBelum ada peringkat
- Contoh Laporan Pengolahan DataDokumen40 halamanContoh Laporan Pengolahan DataIka Agungrizka GufitriBelum ada peringkat
- TOR Peningkatan Kapasitas Petugas Promkes 2013Dokumen5 halamanTOR Peningkatan Kapasitas Petugas Promkes 2013rahmadiBelum ada peringkat
- New Buku Emo DemoDokumen58 halamanNew Buku Emo DemopkmlumbangBelum ada peringkat
- Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja Dan LansiaDokumen110 halamanBuku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja Dan LansiaemilBelum ada peringkat
- Kak Survey PHBS RT 2022Dokumen5 halamanKak Survey PHBS RT 2022puskesmas plandaanBelum ada peringkat
- Materi Kawasan Tanpa RokokDokumen5 halamanMateri Kawasan Tanpa RokokAgeng Kuncoro100% (1)
- SOP PendampinganDokumen3 halamanSOP PendampinganNung AsfBelum ada peringkat
- Laporan Komunikasi Kesehatan Bumil SehatDokumen3 halamanLaporan Komunikasi Kesehatan Bumil SehatagungBelum ada peringkat
- V7 Kebijakan Posyandu - Pelatihan KaderDokumen28 halamanV7 Kebijakan Posyandu - Pelatihan KaderAngga BayuBelum ada peringkat
- Notulen Survey Mawas Diri PPDokumen1 halamanNotulen Survey Mawas Diri PPKadek BetrianiBelum ada peringkat
- Proposal TesisDokumen13 halamanProposal TesisDian OktaBelum ada peringkat
- Formulir Pelacakan Resiko Tinggi Dan Kematian NeonatalDokumen4 halamanFormulir Pelacakan Resiko Tinggi Dan Kematian Neonatalwayan sudarsanaBelum ada peringkat
- Laporan Akhir GermasDokumen21 halamanLaporan Akhir GermasannissadevipermataBelum ada peringkat
- Penyuluhan - Anemia - Remaja - Putri Kartika PDFDokumen12 halamanPenyuluhan - Anemia - Remaja - Putri Kartika PDFas'ad saidBelum ada peringkat
- Makalah Promosi Kesehatan (Buk Dona)Dokumen9 halamanMakalah Promosi Kesehatan (Buk Dona)Reni PitalokaBelum ada peringkat
- KAK Advokasi SekolahDokumen3 halamanKAK Advokasi Sekolahpuskesmas cijerahBelum ada peringkat
- B. Tangga Dan Komponen STBMDokumen26 halamanB. Tangga Dan Komponen STBMmariska tiranda deaBelum ada peringkat
- KAK Pembinaan-Pengukuran UKBMDokumen7 halamanKAK Pembinaan-Pengukuran UKBMamien muhamadBelum ada peringkat
- Surat Undangan MMD 2018Dokumen7 halamanSurat Undangan MMD 2018suardiBelum ada peringkat
- Modul Latih Pemberdayaan Masy. STBM StuntingDokumen71 halamanModul Latih Pemberdayaan Masy. STBM StuntingElisBelum ada peringkat
- Modul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting-A4rev170218 PDFDokumen180 halamanModul Pelatihan Fasilitator STBM-Stunting-A4rev170218 PDFSafaBelum ada peringkat
- SPM Puskesmas Sukadiri1Dokumen68 halamanSPM Puskesmas Sukadiri1Adithyar Rachman100% (2)
- Lampiran Perbup JampersalDokumen12 halamanLampiran Perbup JampersalAdithyar RachmanBelum ada peringkat
- Materi Lembar Balik DBD (Demam Berdarah Dengue)Dokumen19 halamanMateri Lembar Balik DBD (Demam Berdarah Dengue)Mokhamad Suyono Yahya100% (10)
- Form Permintaan Obat KeswaDokumen2 halamanForm Permintaan Obat KeswaAdithyar RachmanBelum ada peringkat
- Template SPM Puskesmas .......Dokumen56 halamanTemplate SPM Puskesmas .......Adithyar RachmanBelum ada peringkat
- Materi Pa Kadis Pertemuan TPKJM Nov 20151Dokumen54 halamanMateri Pa Kadis Pertemuan TPKJM Nov 20151Adithyar RachmanBelum ada peringkat
- NOTULENSI Rapat Persiapan DeklarasiDokumen3 halamanNOTULENSI Rapat Persiapan DeklarasiAdithyar RachmanBelum ada peringkat
- Desa Siaga Sehat JiwaDokumen29 halamanDesa Siaga Sehat JiwaAdithyar RachmanBelum ada peringkat
- Laporan Kesehatan KerjaDokumen8 halamanLaporan Kesehatan KerjaAdithyar RachmanBelum ada peringkat
- Rab Pembuatan Septiktank Serasi 2017Dokumen1 halamanRab Pembuatan Septiktank Serasi 2017Adithyar RachmanBelum ada peringkat
- Format Laporan DBD Untuk PKMDokumen9 halamanFormat Laporan DBD Untuk PKMAdithyar RachmanBelum ada peringkat
- Format Laporan DBD Untuk PKMDokumen9 halamanFormat Laporan DBD Untuk PKMAdithyar RachmanBelum ada peringkat
- REVIEW TOT STBM - STUNTING HR 1Dokumen24 halamanREVIEW TOT STBM - STUNTING HR 1Adithyar RachmanBelum ada peringkat