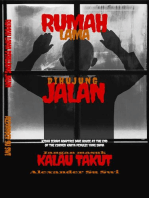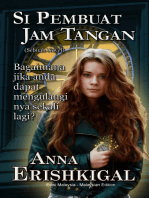Kakek Dan Cerita Cerita Lainnya Eko Triono
Diunggah oleh
al-majnunJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Kakek Dan Cerita Cerita Lainnya Eko Triono
Diunggah oleh
al-majnunHak Cipta:
Format Tersedia
Kakek
SETELAH ULANG tahun ke-23 yang diyakinkan dengan
ucapan panjang umur, Pemuda E. duduk di balkon
kamarnya di lantai 2 pada pagi hari yang cuacanya
diaduk rata bersama dingin. Ia, secara serius, melihat
tiga orang kakek. Kakek pertama sedang mengorek-
ngorek bak sampah dengan pengait besi milik bajak
laut; yang dirambati parasit-parasit lengket dan amuba
yang berkembang biak dengan membelah diri. Dia
menyandang dua wadah. Rantang bergait sebagai
tempat makanan sisa yang masih layak baginya;
nampak potongan pizza yang dirubuti lalat, dan, putih
nasi yang telah berlemak, lalu beberapa biskuit sisa
orang-orang yang sibuk di tengah malam. Bau busuk
seolah tak menjangkau ke hidungnya. Dan karung
bekas untuk rongsok—isinya baru seperempat. Kakek
kedua tidak jauh usianya. Kulitnya lebih keriput,
mengendur menjelma pakaian abadi yang telah lama
Eko Triono __1
dikenakan, tak bisa disetrika, diganti, atau dihaluskan
lagi. Dia menuntun sepeda ontel yang sama rapuhnya
dari arah barat gang, mengenakan topi rajut hitam—
mungkin berbahan rotan—, dan berjalan menunduk
tanpa bicara. Padahal, di boncengan sepedanya ada
dua keranjang bambu yang berisi celengan aneka
jenis yang terbuat dari tembikar; ayam dengan leher
panjang dan berjengger emas, babi dengan taring hijau
dan bersayap burung merak yang kilaunya kebiruan,
harimau dengan tanduk kijang keperakan, dan angsa
emas berkaki naga—yang warna-warninya seperti
balon udara di sebuah karnaval. Itu dagangan. Dan
ia tidak menawarkannya. Kakek ketiga terlihat lebih
bahagia. Ia berada di atap rumah tetangganya. Ia sedang
melanjutkan pekerjaannya yang kemarin; serabutan
memperbaiki atap bocor atau mengambil bangkai-
bangkai tikus yang telah diracun. Sesuatu jatuh di atap
seng. Gigi palsunya. Dia menolah-noleh. Pemuda E.
menarik diri, takut kakek itu malu. Setelah beberapa
menit, diperhatikannya lagi. Pagi masih malas untuk
sibuk—mungkin kerena akhir pekan. Sementara
kakek-kakek itu bekerja, mengorek sampah, menuntun
dagangan dengan lamban, memberbaiki atap dengan
gemetaran, seorang nenek muncul dari arah timur
dan menggendong cucunya sambil menyanyikan
lagu potong bebek angsa. Cucunya seperti baru selesai
mandi, meruapkan harum bedak dan segar minyak
kayu putih. Cucunya mengenakan topi penerbang
yang terbuat dari wol dan kaos kaki bermotif lebah.
Seketika, saat tiba di depan rumah tempat kakek ketiga
bekerja, dia berkata pada cucunya, Mana kakek? Mana
Kakek? Berulang-ulang dengan nada yang disesuaikan
2__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
dengan cucunya yang baru belajar mengenal kata.
Nenek mengarahkan tangan ke arah kakek ketiga yang
kini telah tersenyum, membersihkan tangan, dan
berniat untuk turun dari atap, menggendong cucunya
barang sejenak. Tetapi cucunya tidak menoleh ke arah
nenek dan kakeknya, yang kini, mereka menyelangi
diri dengan entah membicarakan apa. Cucunya justru
menunjuk-nunjuk, setengah melonjak, dan tertawa
dengan memperlihatkan gusi merah pucat dan dua
gigi susunya yang putih ke arah kakek pertama, yang
sedang mengorek-ngorek sampah tak jauh dari situ.
Kakek pertama menanggapinya dengan riang, tulus,
dan bahagia; ia menaik-turunkan plastik-plastik
sampah dengan tongkat besi bajak lautnya, sehingga
menyerupai burung-burung yang sedang beterbangan
di angkasa. Sementara itu berlangsung, kakek kedua
sampai melintas dengan dagangan celengannya yang
berbentuk hewan-hewan ajaib. Cucu itu tersenyum
ke arahnya. Kakek kedua menanggapi dengan diam
saja; hanya melihat sebentar pada cucu itu. Namun,
tanpa diduga sama sekali, kakek kedua kemudian
menyempatkan diri untuk melepas salah satu pegangan
stang sepedanya, menutupkan telapak kanannya ke
wajah, dan melepasnya kembali dengan tersenyum,
seolah berkata: cilukba—yang sejenak dan membuat
cucu itu semakin tergelak menunjuk-nunjuk celengan
yang warnanya seperti dunia. Neneknya nampak
marah, Itu kakekmu! Itu! Nenek mengarahkan kepala
cucunya, dengan paksa, pada kakek ketiga—kakeknya
yang sebenarnya—yang mulai mendekat dan bersedia
menggendongnya dengan hati senang. Dan dua kakek
yang lain, pura-pura tak melakukan apa pun; mereka
Eko Triono __3
pura-pura masih sangat sibuk bekerja, dan pura-pura
sedang berjalan murung mencari rezeki seperti hari-
hari biasa yang sunyi.[*]
4__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Ikan Kaleng
SAM TIGA hari di Jayapura; dia guru ikatan dinas
dari Jawa. Dan Sam tak mengira, saat pembukaan
penerimaan siswa baru buat SD Batu Tua 1 yang
terletak sejurus aspal hitam dengan taksi (sebenarnya
minibus), ada yang menggelikan sekaligus, mungkin,
menyadarkannya diam-diam. Ia tersenyum mengingat
ini.
Ketika seorang lelaki bertubuh besar, dengan tubuh
legam, dan rambutnya bergelung seperti ujung-ujung
pakis lembut teratur menenteng dua anak lelakinya,
sambil bertanya, “Ko pu ilmu buat ajar torang (kami) pu
anak pandai melaut? Torang trada pu waktu. Ini anak
lagi semua nakal. Sa pusing.”
Sam memahami penggal dua penggal. Dia, seperti
yang diajarkan saat micro teaching, mulai mengulai
Eko Triono __5
senyum lalu berkata, “Bapak yang baik, kurikulum un-
tuk pendidikan dasar itu ketrampilan dasar, matematika,
bahasa, olahraga, dan beberapa kerajinan...”
“Ah, omong ko sama dengan dong (dia) di bukit
atas! Ayo pulang!”
Kaget. Sam tersentak, belum lagi dia selesai. Dan
ini tak pernah diajarkan di pengajaran mikro. Juga di
buku diktum bab penerimaan siswa baru. Dia pucat;
diraihnya segelas air putih.
Pedaftar pertama memantik rasa sabar dan sesuatu
yang asing dalam dirinya. Dia bersabar menunggu detik
berikutnya dari lepas pukul sembilan. Dia mengelap lagi
wajahnya. Di meja pendaftaran samping, kosong, Tati
belum datang. Cuma ada Markus, Waenuri, dan Tirto—
teman sekelasnya, yang sedang bertugas masing-masing
di ruang lain; mulai dari siap berkas, mencatat kebutuhan
anggaran, dan menyiapkan papan tulis. Bismillah, ia
mengharap, tepat ketika sebarisan orang-orang legam
bertelanjang kaki menjejaki halaman yang setengah
becek bertanah merah, dilatari sisa-sisa alat berat dan
bekas pengadukan material bangunan itu.
Dan syukurlah, meski dengan penjelasan yang tak
kalah berat; setidaknya, tak ada yang seperti orang
pertama. Begitu seterusnya sampai Tati tiba membantu.
Tapi ia masih penasaran, siapa sebenarnya orang itu. Ia
coba mencari tahu, hasilnya, ternyata lelaki pertama
tadi adalah kepala suku Lat, berada di sekitar pantai
sebelah kanan, diperlukan lebih dari seratus rengkuh
dayung untuk sampai di kampungnnya yang ada di
laut. Kira-kira begitu kata orang-orang yang juga ada
berasal dari sana.
“Trada perlu risau, dong itu memang keras kepala,”
6__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
kata si penjelas itu sambil berbisik-bisik, takut ada yang
melaporkan omongannya.
II
HARI TADI tercatat dua puluh satu siswa mendaftar
jadi angkatan baru, sekaligus kelas baru buat sekolah
itu. Usia mereka beragam. Hari berjalan, minggu
silih, dan bulan menumpang tindih. Tepat memasuki
bulan Agustus, keganjilan itu muncul kembali. Meski
sebelumnya pernah terjadi, tapi kali ini semakin sering.
Dua anak itu sering muncul di halaman. Mereka
nampak memandangi seusuatu yang mungkin aneh
baginya. Teman-teman lain menghadapai sebuah tiang
dengan bendera dua warna. Berbaris lalu menyanyi-
nyanyi. Dari sini, Sam merasa iba. Ia dekati. Dan tahu
betul, mereka itu yang tempo hari dibawa oleh kepala
suku Lat.
“Kenapa kalian, ingin seperti mereka?”
“He-eh...,” yang satu mengangguk. Ia menatap
teman-temannya yang menyanyi-nyanyi bersama itu,
dari sana terbalas, dua tiga melambai ke mereka yang
ada di dekat jalan depan sekolah itu.
“Apa ko ini Do! Trada boleh!! Bapa Ade bisa marah.”
Mereka kemudian berlari menjauh, menurun di
bukit-bukit kecil bercadas, berkelok, samar dan hilang
bersama suara angin dan pemandangan hijau hutan
juga beberapa rumah penduduk dan sekali dua waktu
minibus berlalu dengan muatan penuh.
Sam memutuskan sore nanti ia akan mengunjungi
rumah anak-anak itu dan memberikan semacam pen-
jelasan.
Dengan dibantu salah seorang wali murid, sampailah
Eko Triono __7
dia di rumah lelaki itu. Sam kemudian menyampaikan
maksud dan sejumlah penjelasan, tertutama perihal
anak-anak mereka yang sering datang ke sekolah.
“Ko trada perlu ajari torang. Torang dah pu sekolah
sendiri. Lihat mari! Justru murid ko yang mari.”
Sam, setengah tak percaya, mengikuti lelaki itu. Ia
turun dari rumah besar, lalu menuju perahu di antara
barisan rumah-rumah, aroma laut menebar, hidungnya
disesaki asin, dan matanya dipenuhi tatapan aneh dari
penduduk sekitar. Dia menuju sebuah rumah yang sama
di atas laut, dan nampak sudah dua anak lelaki yang
menyambanginya siang tadi. Dan, beberapa muridnya
yang ia kira sakit, ternyata ada di sana.
Di tempat ini, terlihat: barisan dayung-dayung yang
digantung, tombak bermata tajam, sebuah perahu
ditengah ruangan, jala, pisau, titik-titik pada cangkang
karang, yang kemudian Sam tahu itu rasi bintang di lan-
git. Lelaki Lat menjelaskan lagi, dengan bahasa alihkode
semi kacau, bahwa di sinilah sekolah yang ia dirikan.
Sekolah yang diberinama Lat: sesuai nama suku.
Sebenarnya lelaki tadi tidaklah telalu bodoh. Ayahn-
ya dulu pernah menyekolahkannya ke “sekolah pemer-
intah” meski hanya di kelas satu—demikian mereka
menyebutnya, namun suatu hal mengganjal. Ketika
itu, kakaknya, yang sudah kelas enam di SD Jayapura 2
tak bisa apa-apa ketika harus menemani kakak mereka
yang lebih tua pergi melaut menggantikan ayahnya yang
sakit keras. Dia, kakaknya yang SD tersebut, hanya bisa
omong dan menyanyi-nyanyi, lalu pamer angka-angka
tak jelas dalam kertas, tapi ia tak becus membaca rasi
bintang, arah angin, membelah ombak, mengarah tom-
bak, apalagi mencecap asin air dan jernih gelombang
8__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
untuk menerka di mana ikan-ikan berkumpul. Dari
situ ia benci sekolah—ia benci menghabiskan waktu
dengan menyanyi dan menggambar tidak jelas. Dan,
pelak, ketika ada pembukaan sekolah baru, ia selalu
mencari sekolah yang mengajarkan anaknya melaut,
membelah ombak, mendayung membaca rasi bintang,
menombak ikan paus, dan seterusnya. Dan itu tak ada,
atau mungkin tak akan pernah ada!
Sam terdiam. Ia paku bagi kelana: semua diktum
terkulum gelombang di kaki pancang; berpias-berpias.
Dan sorenya juga, Sam melihat di bawah cahaya
senja yang senantiasa keemasan sebelum muram jadi
gelap, lelaki itu mengajar dua anaknya dan tiga dari
muridnya yang belakangan absen. Dia mengajari cara
memegang dayung, menggerakkannya kanan kiri di
atas perahu di tengah kelas itu. Dan tak sekalipun lelaki
itu memukul atau bahkan membentak bila salah. Dia
selalu berkata,
“Ko pasti bisa! Ko dilahir atas laut, makan ikan laut,
garam laut, ko anak laut! Laut ibu torang. Kitorang
cintai, dayungi, dan ciumi angin asin ini. Laut tempat
ko makan, laut tempat ko besar nati, ko paham sa pu
nasehat? Ini tujuan ko sekolah di Lat, ko belajar hidup.
Bukan cuma omong kosong dan menggambar. Ko di-
titipi laut Bapa Kitorang.”
III
PERISTIWA DUA tahun silam terngiang makin dalam,
di meja kelas, ketika kini dia menghadapi pesan pendek
berisi keluhan dari sejumlah kawan di Jogja yang belum
juga mendapat kerja. Dia menarik nafas. Untung dia
Eko Triono __9
dapat ikatan dinas; meski jauh seperti ini, terpisah dari
keluarga.
Dia sedang memeriksa kehadiran, saat tiba-tiba
lelaki kepala suku Lat itu datang mengetuk pintu kelas.
Dia izin sebentar pada murid-muridnya yang kini ting-
gal setengah—sisanya “sekolah” di Lat: memilih belajar
membelah ombak dengan benar, membaca rasi bintang
dengan sket cangkang kerang, dan seterusnya.
“Maaf, ada yang bisa saya bantu, Pak?” Sam bertanya,
dalam hati ia mengira lelaki itu, yang kini membawa
kedua anaknya beserta sejumlah anak lain, ingin menye-
kolahkan di tahun ajaran baru yang sebentar lagi tiba.
“Ko orang Jawa, bisa ajar torang buat ini?”
Sam mundur sedikit. Ia kaget. Lelaki itu menunjukan
ikan kalengan bermerek sarden.
Usut punya usut, setelah bercakap kemudian, se-
kolah Lat tengah mengalami masalah. Murid-muridnya
bertambah banyak, orang-orang di Batu Tua lebih me-
milih menyekolahkan anaknya di sana, yang dalam wak-
tu tak lebih dari setahun dapat membantu menangkap
ikan. Yang mengajar juga orang-orang mereka sendiri
yang berpengalaman. Nah, dari sana jumlah ikan hasil
tangkapan naik deras. Ketika kepala suku Lat itu pergi
ke Jayapura untuk memasar ikan, ia melihat ikan kaleng
yang ternyata harga sebuahnya setara dengan harga satu
kilogram ikan mentah. Dia terkejut. Padahal, menurut
kepala suku Lat itu, satu kaleng hanya berisi dua tiga
potong. Dari sini dia ingin menemui sekolah yang bisa
mengajarkan “murid”-nya membuat ikan kaleng.
Dan, sekali lagi Sam menggeleng. Ia menjelaskan
kembali tentang standar pengajaran di sekolah, kuri-
kulum, evaluasi, ijasah, dan ketrampilan, menghitung,
10__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
bahasa, menghafal nama mentri, pancasila, undang-
undang dasar...
“Ah, baik. Ko tau tempat buat ini?” kepala suku Lat
menegas. Matanya resah. Anak-anak di belakangnya
tengah membaur bersama anak-anak dalam kelas. Sam
membaca pabrik produksinya yang ternyata di Banyu-
wangi, Jawa Timur.
“Sa mau ke sana! Ko kasih tau....”
Sam terbengong. Dan ia akan makin kaget, jika
tahu bahwa lima hari mendatang, akan ada rombon-
gan kecil dengan perahu layar ukuran sedang, berbekal
peta yang ia berikan sewaktu bertanya, berduyun
mengarungi samudra Hindia, menuju Jawa Timur buat
belajar cara mengalengkan ikan agar tidak rugi dalam
menangkap demikian banyak ikan, agar anak-anak
kelak sejahtera, agar listrik penuh, televisi seperti di
kota, mobil, motor... Tidak ada yang ragu; mereka anak-
anak sekolah Lat; terlatih membelah ombak dengan
dayung, membaca angin, gemintang, dan asin air laut
dan jejak-jejak ikan di antara buih dan gelombang. Jiah!
Khiaak![*]
Eko Triono __11
12__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Kebahagiaan
PAGI HARI pintu kamarku diketuk dengan keras.
Keras sekali. Kubuka dan ada anak kecil. Kutanya,
siapa? “Aku anakmu di masa depan nanti.” Kulihat,
muka dan sisiran rambutnya memang mirip denganku,
tapi caranya memandang dan keangkuhan bicaranya
seperti Bruce Lee. Ada apa? “Boleh aku masuk?” “Ya,
masuklah. Maaf, berantakan,” aku menggeser gelas kopi
kotor yang menimbulkan bau jamur dan ada seekor
cicak di dalamnya, “Aku belum sempat nyuci, banyak
kerjaan. Banyak penindasan yang harus diungkapkan.
Aku bahkan belum kepikiran potong rambut.” Dia
mengangguk-anggkuk—aku tahu sebenarnya dia tidak
tak paham dan memang tidak perlu paham; lagi pula
aku hanya sok berarti bagi sesama hidup—bibirnya
manyun, dan matanya begitu lugu dan arif; dia memiliki
cara memandang seorang maha guru para petarung
di masa yang akan datang. “Itu siapa?” Dia menujuk
Eko Triono __13
foto. “Itu pacarku.” Dia terlihat memastikan, mungkin
menyamakan dengan ibunya. Sedang aku belum
menanyakan kepastian ibunya di masa depan. “Ada
perlu apa? Minta uang jajan?” Dia menggeleng. “Iuran
sekolah?” Menggeleng lagi. “Sepeda?” Menggeleng.
“Lalu?” Dia berbalik, mendekat, dan menatapku dengan
penuh kasih sayang, “Aku cuma ingin tahu masa muda
ayah.” Aku memeluk dan mengusap rambutnya. Pagi
ini, tidak seperti biasa, aku merasa bahagia dan tak ingin
mati muda. Dan di luar, harusnya Tuhan sudah mulai
menurunkan hujan.[*]
14__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Seekor Hiu di Atap Rumah
IA MEMBUKA JENDELA. Seekor hiu, dengan kulit
melembek dan mata mendelik, terkapar di atap rumah
tetangganya. Mulutnya menggigit antena televisi.
Ekornya menggugurkan beberapa genting, menancap
ke dalam ruang-ruang rumah. Sinar pagi membuat
seekor hiu itu tersorot, berpose, seperti aktor yang
mati di tengah panggung. Kabel-kabel, dari kabel
listrik hingga kabel jemuran, digelantungi kepiting
aneka jenis dan ukuran. Merah kusam, dan dengan
satu capit, mereka memperagakan adegan pemanjat
akan jatuh dari jembatan gantung pada suatu hari,
hingga talinya melengkung, seperti busur yang mau
melecut.
Selebihnya, rumput-rumput laut dan sampah plas-
tik, juga sebat-sebat kain saling sengkarut.
Jam pengingat berdering (memang waktunya). Ia
dengar suara sendiri mengingatkan soal ini dan itu:
Eko Triono __15
“Selamat pagi diriku. Ingat hari ini: laporan
keuangan, memotong kuku, bertemu dia jam lima sore
di kafe romantis, membeli detergen, pemutih, kopi,
dan....”
“....Dan menyiram bonsai pohon kenangan,” klik.
Dimatikannya jam pengingat.
Ia bersenandung menuju kamar mandi. Lagu lama
dari The Beatles. Ia suka John Lennon, tapi tidak suka
politik, apalagi kaca mata hitam. Ia suka dia sebagai dia
yang kesepian dan bergairah pada cinta yang subversif.
Ia mendapati perwakilan otentik dalam diri yang sep-
erti itu. Kemudian, ia mulai berpikir tentang kafe pada
jam lima sore, sembari menuju kamar mandi, mem-
bayangkan beberapa dialog mesra, lelucon positif, dan
kalimat-kalimat yang akan memperbaiki hubungan di
antara mereka, dan tepat ketika itu seekor penyu dewasa
merangkak dari arah lemari pendingin menuju bawah
meja makan dengan cara kamuflase serdadu menuju
tempat perlindungan. Sebagian tempurungnya sompal.
Namun, masih bersemangat.
Cahaya memang mendadak begitu melimpah di
dapur dan kamar mandi, sehingga ia tak perlu memberi
kehidupan pada sebuah lampu bohlam.
“Kapan terakhir aku menemani anak-anakmu ber-
main ular tangga? Bulan lalu? Tahun lalu?”
(Suatu kemungkinan reaksi).
“Aku tahu, kau tidak suka mengingatnya. Maafkan
aku. Apa kau tidak kesepian?”
(Suatu kemungkinan reaksi).
“Baiklah. Boleh aku menyampaikan sebuah lelucon
agar kau bisa tertawa dan terlihat bahagia? Tentang
presiden yang bunuh diri karena cintanya ditolak oleh
16__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
seorang nenek-nenek?”
Ia kian membayangkan pertanyaan, sebuah se-
nyuman, dan perhatian yang sungguh-sungguh akan
dipertahankan dalam dirinya pada jam lima sore nanti,
apapun yang terjadi. Apapun.
IA MEMBUKA KRAN air. Pasir-pasir ikut keluar. Bau
laut merendam bak mandi yang airnya menghitam
seperti comberan. Ia periksa. Tetes-tetes tinta gurita
penyebabnya. Di atas sana. Di atap kamar mandi yang
telah bobol ditambali biru langit seacara mengesankan.
Beberapa gurita lunglai, mungkin ketakutan sampai ke
alam ruh avertebrata, hingga tintanya terus menetes,
seakan mau menuliskan suatu pesan dari harapan yang
dirahasiakan.
Ia membuka jalur penguras bak, dan menyodok
bangkai-bangkai gurita dengan gagang sapu.
Tapi air macet. Ada ubur-ubur kecil dengan tentakel
bersijerat, cumi-cumi, ikan-ikan kembung, kuda-kuda
laut tanpa kendali, dan planton-planton yang meny-
umbat di dasar bak.
“Kau suka seafood?” Ia akan bertanya dan mengajak,
“kita bisa memasaknya bersama.”
Ia memang berencana, setelah ini, akan mencari re-
sep saus tiram. Dan, dengan gairah jam lima sore nanti,
ia menangkapi mahluk-mahluk laut di bak mandi itu,
menampungnya pada ember, dan akan menyimpannya
biar tetap segar.
Eko Triono __17
KETIKA IA MEMBUKA lemari pendingin, sejumlah
nyamuk ia temukan membeku dalam keadaan terbang
tersangga stalaknit es.
Bukan hanya itu, lima ekor tikus jadi batu es abadi
dalam pose menggigit buah jeruk, apel, dan mentimun.
Ia tersenyum kecil, “Kuharap kalian begini bukan karena
kutukan Tuhan dari surga, tapi pilihan kalian sendiri.”
Sementara kecoak-kecoak jadi mayat es di atas puding,
serta beberapa, bersama serangga lain, membeku di
sekitarnya, menempel pada dinding lemari pendin-
gin, mengingatkannya pada diorama miniatur pahla-
wan dan pertempuran di suatu museum peringatan
kemerdekaan,di seluruh negara di belahan dunia ini.
Begitulah kira-kira.
Ia sempat mencari. “Kekuatan macam apa yang
membuat serangga-serangga ini mampu masuk ke
dalam lemari es?” Ia menerka. Mungkin dari arah kipas
bawah, atau saluran kabel, atau....
“Tapi kumohon, lebih baik jangan tidur di sini,
Teman-teman. Bumi Tuhan itu luas. Ya, setidaknya
kalian tidak perlu uang dan kartu tanda penduduk.
Kumohon, pergilah dengan bahagia.”
Ia mencongkeli, dan, meletakan mereka yang mem-
beku itu pada tempat yang semestinya, dengan sangat
hati-hati. Sehingga udara kemudian membantu mem-
bangkitkan mereka secara perlahan.
“6.45, bersiap sarapan pagi, memompa sepeda, dan
menyemir sepatu,” teriak jam pengingat.
“Iya, Nyonya Tua, mengertilah perasaan anak muda.
Atau kucopot bateraimu!”
Dia melanjutkan mandi di bawah atap yang ber-
lubang dan ditambal oleh langit berkabut kelabu.
18__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
IA MEMBUKA PINTU depan dengan susah payah,
karena baling-baling kapal seekuran kipas raksasa, dan,
sebuah sekoci yang miring, menghadang di sana. Hanya
dapat terbuka setengah. Ia menyelinap. Aroma laut
semakin kuat. Lumpur yang diluapkan dari dasarnya
hadir melabur cuaca yang semestinya. Ia mengambil
sepeda dan memompa. Di sisi kanan, sebuah kapal
berhenti tepat satu meter dari rumahnya. Rumah-
rumah yang lain tinggal puing. Tumpukan batu bata.
Atau, jebol di sana-sini. Atau tegak berdiri dengan ikan
hiu di atap, pintu, jendela, atau menampakkan lumba-
lumba dengan moncong panjang yang terbaring di atas
kotak pos surat penuh lumpur.
Ia mengambil bonsai pohon kenangan dan meleta-
kannya di keranjang sepeda. Ia memang benar-benar
bersepeda, dengan pakaian kantor rapi, dan berkas
lengkap, seperti hari-hari sebelumnya, memasang
headphone dengan lagu-lagu lama dari The Beatles, dan
mengingat jam lima sore. Ia melintasi jalanan beran-
takan. Genangan air berlumpur. Kepiting-kepiting
yang mencapit ikan mati atau sesama jenisnya. Dan
berhenti sejenak memperhatikan ikan paus raksasa
yang telentang.
“Besar sekali,” ia memperhatikan. Lambungnya
lembek keabu-abuan dan sobek.
Dan, dari sobekan itu, keluar ikan-ikan kecil yang
insangnya masih menunjukan gejala hidup.
Ia ingin mengambil buat tambahan persediaan,
seandainya ia tadi membawa wadah.
“Dari mana kau dapat ikan-ikan ini?” dia pasti akan
bertanya begitu.
“Siapkan dirimu untuk suatu kejutan....”
Eko Triono __19
“Tidak ada yang lebih mengejutkan bagiku kecuali
kabar bahwa suamiku bangkit dari alam kubur.”
“Aku memasuki perut ikan paus yang lembek
dan mengambil ikan-ikan kecil yang terperangkap di
dalamnya. Apa itu tidak mengejutkan?”
“Setidaknya kau akan dipanggil pahlawan oleh ikan-
ikan kecil itu. Mintalah pujian pada mereka. Jangan
padaku.”
“Kau dingin sekali,” ia menyantapnya, bergelepotan,
dan sesaat kemudian berkata lirih dengan menatap.
“Seperti sejarah.”
“Atau sebaliknya: sebenarnya kaulah yang terlalu
bersemangat, seperti revolusi, seperti demokrasi, sep-
erti....”
“Ssst. Seperti seharusnya cinta yang selalu ingin
segera sampai.”
Ia masih asyik melaju ketika serombongan orang
dengan pakaian seperti robot, seperti astronot, meng-
hentikannya dengan terlalu sopan untuk disebut seba-
gai sebuah penangkapan.
Dan dengan pengeras suara, dari jarak yang cukup
untuk menjajar sepuluh mobil, salah seorang bicara
dengan nada dibuat-buat baik: “Selamat pagi, Tuan.”
Ia terpaku, tanpa turun dari sepeda.
“Maaf, Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tu-
buh Anda telah sepenuhnya terkontaminasi radio aktif.
Tsunami telah membuat reaktor di kota ini pecah. Dan,
kami sungguh tidak mengira, masih ada yang selamat
seperti Anda. Namun demikian, Anda kini telah jadi
‘sesuatu’ yang tidak semestinya. Jadi....”
Ia tidak mengerti (mungkin sebenarnya tidak mau)
apa yang diucapkan oleh orang-orang dengan paka-
20__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
ian pelindung seperti robot itu. Yang ia tahu, mereka
menghalangi dengan cara pasukan monster misterius
dari planet lain. Menyebalkan sekali: apa mereka tidak
tahu kalau ia harus segera menyampaikan laporan
keuangan ke kantor penerbitan, dan menemui dia jam
lima sore di kafe romantis.
Karenanya, ia membalik arah dengan cekatan. Ia
melaju kencang diantara onggokan ikan hiu, luapan
lumpur, puing-puing dan kepiting yang berseliweran;
yang berjalan miring dengan mencapit bangkai-bangkai
sesama jenisnya dalam pose yang seakan telah terbiasa,
seakan telah manusia.
Tak lama lagi, ia akan menemui laut dengan kapal-
kapal kosong, ombak yang malas, dan bau ruh di dalam
buih. Tentu sebelum segalanya berakhir, dan, tak ada
lagi jam lima sore.
Dan ia sedang ingin menanyakan padanya, “Apa
yang kau suka dari laut? Airnya, pasirnya, atau kenangan
diantara keduanya?”
Ketika tiba-tiba ada hujan sederhana dengan lumpur
dan disertai udang dan kepiting, meski hanya sejenak,
namun cukup untuk membuat jalanan seakan merayap,
seakan dipenuhi para demonstran menuntut turunnya
seorang diktator. Bajunya kotor. Beberapa udang dan
lumpur menempel di rambut dan tengkuknya. Namun,
ia terus melaju dengan headphone, lagu-lagu lama dari
The Beatles, dan sebuah bonsai pohon kenangan di
keranjang depan, yang telah berbunga kepiting serta
udang-udang kecil yang meloncat-loncat riang dalam
balutan lumpur laut.[*]
Eko Triono __21
22__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Sekarang Jam Berapa
SEKARANG JAM dua belas, dan tak ada hujan turun,
dan, aku sudah menunggu di sini sejak jam sembilan
pagi. Tapi ia belum datang. Pelayan tua itu kembali,
“Ini biar lebih romantis.” Dia membawakan lilin
putih dengan tatak keperakan, menyalakannya,
lalu, mengajakku membicarakan banyak hal sambil
menanti. Dia bertanya perihal janji yang demikian
lama. Kukatakan, setiap janji harus ditepati, kupikir
memang demikian, tentu, di samping rasa cinta yang
masih menggelora dalam batin yang membuatku harus
menunggu. Orang tua itu tertawa, dan, giginya yang
perak terlihat bagai potongan medali, atau, memang
sengaja diperlihatkannya untuk unjuk diri; bahwa dia
pemilik kafe yang hidup bahagia meski tanpa cinta
pertama. Rambutnya sudah putih. Pakainnya pun ikut
letih. “Kalian dulu memang selalu kemari, aku ingat
itu. Tapi, apa kau tidak pernah dengar istilah cinta
Eko Triono __23
sejenak?” Istilah ini membuat emosi. Aku diam. Dan
dia malah terus bicara, “Perempuan mudah berubah
perasaannya, mudah kesepian, dan, terlebih perempuan
yang egois, mudah mengganti rasa cinta dan membuat
ribuan apologi untuk berkhianat. Tak ada cinta sejati
di hati perempuan yang demikian....” Aku ijin keluar,
ingin membunuh omongannya yang semakin tak jelas
itu. Di luar, pasar yang tertib telah bubar. Tinggal sisa
dan jalan raya yang selalu padat oleh kepergian. Dan,
kupastikan di sekitar, tak ada tanda-tanda. Akupun
masuk dan kembali duduk menunggu: berhari-hari,
berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga bertahun-
tahun di dalam kafe ini. Pelayan tua, yang sudah
lama mati itu, diganti oleh keturunan-keturunannya;
mengganti jaga, dan, menggantikan bercakap-cakap
menemani kesunyianku. Aneka makanan dan mata
uang bertukar jenis. Kereta-kereta lewat diganti dengan
baru. Kendaaran berganti merk. Jalanan berganti
marka. Rumah-rumah berganti bentuk dan warna.
Tapi ia tetap tak datang menepati janji. Barangkali
ia telah lupa, barangkali dulu kuliahnya, kemudian
pacar-pacarnya, kemudian suaminya, kemudian anak-
anaknya, kemudian cucu-cucu, dan kesehatannya
telah membuat lupa pada janji yang dengan sumpah
diucapkannya, tepat di telingaku yang dulu masih peka,
yang kini mulai terganggu, dan tak jelas lagi. “Kami kira,
anda harus pulang, Kek....” Cucu almarhum pelayan
tua berkata padaku dengan muka berteriak tapi terasa
lirih. Aku sadar betul, usia melucuti tubuhku seperti
korosi pada besi, namun perasaanku masih semuda
dulu, kataku. Cucu itu, yang juga seorang perempuan,
tersenyum manis, “Anda menghabiskan tahun-tahun
24__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
terbaik hanya untuk menunggu sesuatu yang tak
berguna sama sekali? Ini lelucon paling biadab dari
perasaan, Kek.” Ia tak tahu soal janji. Ia bawakan kopi.
Tangan dan kepalaku terasa retak dan rentan. Aku
benar-benar sudah renta, dan, barangkali mautpun
tengah menungguku dengan cara yang sama. “Pulang,
berbahagialah dengan sisa usiamu. Cinta sesungguhnya
hanyalah antara kita dan diri kita sendiri.” “Pulang?
Di mana rumahku?” “Rumah Kakek juga ada dalam
diri Kakek sendiri yang jernih, yang bahagia,” kata
perempuan manis itu cerdas sekali. Aku terpukau
dan terpukul sekaligus. “Tidak, terimakasih, aku akan
tetap menunggunya di sini, rumahku hanya ada dalam
cinta dan kesetiaan padanya!” Gadis manis itu terdiam,
mungkin sebagai perempuan dia mampu merasakan
penderitaanku. Bumi yang semakin tua ataukah aku
yang hampir mati? Tak lagi bisa kubedakan. Pikiranku
kusut. Tengah malam aku bangun di bangku kafe yang
sudah delapan belas kali diganti itu; aku bermimpi ia
datang! Untuk pertama kalinya aku bermimpi tentang
ia. Ia masih muda sekali, manis, hanya tubuhnya yang
makin kusut, perutnya membesar, cahaya matanya yang
dulu kuat hilang dilucuti seseorang pada usianya yang
ke-21, barangkali di suatu kamar, atau di rumahnya
saat sepi. Segera kubangunkan gadis penjaga kafe.
“Ia datang, Nak, ia datang!” Dia terkejut. “Ia sudah
datang. Aku akan pamit pulang, ini, ini bon terakhirku.
Terimakasih untuk semuanya,” kataku lagi, dan, coba
bergegas. “Datang? Mana? Tak ada siapapun. Anda
baik-baik saja ‘kan, Kek?” Dengan lembut, dengan
sentuhan yang seakan pernah kukenali, didamiknya
pundakku yang mulai bungkuk, lalu, keningku yang
Eko Triono __25
berkerut dan diderasi keringat; kemudian, lagi,
diusapnya perlahan-lahan. “Ya. Datang. Ia telah datang.
Ia berubah. Berubah. Ia beda! Dan kau; kau tidak akan
bisa melihatnya.” Gadis itu agaknya tak mengerti apa
yang kukatakan, dan, bertanya sebabnya tak bisa.
Dengan disertai gemetar sisa dari cemasnya keyakinan
yang coba untuk tugur, kukatakan padanya, “Kau tidak
bisa melihat kehadirannya. Tidak. Tidak akan pernah.
Karena kau perempuan, kau bukan seorang lelaki yang
mencintainya dengan sepenuh hati....” Seketika gadis itu
memeluk tubuhku erat sekali, membuat jiwa ingin mati
hari ini, hari Jumat, hari delapan belas bulan Oktober
yang pucat, lembab, dingin dan teramat pasi.[*]
26__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Tahun-tahun Penjara
I
Saat kau menyaksikan algojo kekar mengacung rotan,
setelah hakim mengetuk jumlah cambukan, dan
temanmu—dengan sebebat kain putih, mungkin
bertanda suci atau penyucian, di pinggangnya, sebagai
cawat—berjalan menuju tiang pasungan dengan gigi
gemeletuk, gemetar, pucat, namun terlihat pasrah, kau
jadi ingat suatu hari di desa, di Pantai Selatan yang
nelangsa.
Ketika itu, ibu telah ambil ancang untuk menghajar
tubuhmu dengan ranting. Ibu membawa ranting pohon
jarak kering; kulitnya telah mlocoh; urat-urat kayunya
melintir seperti bisep seorang petinju. Kau memejam,
tahu akan ada perih, darah, lecet, dan kemudian sunyi.
Dan entah bagaimana, kau terlihat terbiasa.
“Dasar anak tidak tahu diuntung! Sudah baik kamu
kulahirkan ke dunia! Masih saja....”
Eko Triono __27
Seharian tadi, kau bersilah di bawah talang. Hujan
deras, jatuh dengan berat. Monster-monster mulai
bermunculan. Raksasa hijau dengan taring dan liur
api merobohkan segalanya. Desa-desa dihancurkan.
Perahu bergelimpangan. Terbakar. Menjadi asap. Hitam
di udara. Tenggelam di muka gelombang. Penduduk
menjerit. Kau, seorang kesatria yang bertapa di hutan
tersembunyi, di bawah air terjun dengan batu-batu li-
cin, tersentak! Gemanya sampai. Kau pun, sebagaimana
dalam wayang dan film pendekar kesukaanmu, turun ke
jalan maghrib yang rembang. Berhenti dengan jantan di
tengah jalan depan rumah, menghadang. Jangan hadapi
penduduk yang tak bersalah, hadapi aku, aku adalah
musuh bagi siapapun yang memusuhi kebenaran—kau
berkata dengan mendunduk, lalu mendongak, melem-
parkan caping bambu ke arah pohon pisang (dalam
imajimu menancap di sana; suatu tanda kesaktian), dan
mulai memasang jurus mematikan.
Tetapi, tidak lama. Kau dicengkram dari belakang.
Bajumu digait. Kau diseret pada tanah berlumpur. Hu-
jan seolah ikut melemparimu. Dan, kau tahu, sebuah
kayu jarak akan mengalahkanmu sebentar lagi; merun-
tuhkan semua imaji tentang kesaktian.
“Tuan Alex Kanama bin Kanama Hamid, asal dari
Filipina, telah melanggar tertib penjara dengan meny-
impan tembakau di dalam lambung pencernaan, oleh
karenanya harus dicambuk tiga kali. Apa Tuan Alex
Kanama bin Kanama Hamid telah sedia?”
Temanmu, kini, menyerahkan kedua tangannya
pada kayu bercengkeram pemasung. Kau lihat: nafasnya
begitu tertahan. Detik pun jadi rawan.
28__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
II
Dia membelakangi ketakutannya sendiri. Kalian
membatu. Tak ada lagi doa. Doa barangkali sudah lama
cela di tempat ini.
Bahkan mungkin di semua dinding, saat kau atau
orang lain, harus membalik tubuh. Berjaga atas petak
umpet tengah malam bersama sejumlah hantu rahasia.
Pukulan tiba pada sebelah kakimu yang tak tegap, ka-
rena lelah berdiri di dinding kelas, sepanjang pelajaran
dari wali kelas.
“Kalau tidak mau begini, ya bayar iuran sekolah!”
Ibu guru yang sarjana itu memakimu.
Hanya kematian yang membuatmu melupakan peri-
stiwa itu. Lengkap dengan rasa sakit dari kepalamu yang
dijedugkan ke tembok berkali-kali hingga berdengung.
Dan, setelahnya, kau putuskan untuk mencuri uang
ibu di bawah kasur demi membayar iuran, demi tidak
dimaki oleh ibu guru yang sarjana.
Dua belas jam kemudian, ibumu, yang tak mau
kau sekolah, tahu. Kau ditangkap saat sedang mencari
kayu bakar di bawah pohon-pohon salam yang ranting
keringnya paling rapuh di antara pohon-pohon lain di
alam pedesaan.
Kau ditelanjangi. Mendekap pohon nangka bela-
kang rumah; licin, dingin, dan ditumbuhi lumut-lumut
yang tak hijau lagi. Kedua tangan dan kakimu diikat
sebagaimana orang-orangan sawah di musim panen
yang diancam oleh manuver-manuver burung pipit dan
peking kaji dengan mulut mereka yang tajam: runcing
seperti ujung rudal pesawat penghancur. Ayahmu mun-
cul dari balik ketegangan membawa tiga sarang semut
kerangkang yang telah tumbuh di daun mahoni, jambu,
Eko Triono __29
dan pohon albasiah. Kau mejam. Ayahmu bukan tampil
sebagai biksu yang datang membawa pijar-pijar dari
kandil kebijaksanaan. Dan, ini bukan kali pertama! Kau
berharap bisa menjadi ninja jiraiya, bersiaga menge-
luarkan samurai, meloloskan diri dengan melempar
shuriken dan asap, dan membunuh semua orang yang
menyakitimu dengan tusukan tepat di dada kiri mereka.
Namun, segala darimu senatiasa berupa harap yang tak
lekas menjadi iya.
Orang-orang itu terus menaburkan krangkang yang
mengamuk. Jutaan sengat datang menginfeksi kulitmu.
Kau rasakan kematian yang datang hanya untuk iseng.
“Nanti jangan mau diobati. Obat itu sebenarnya
racun yang membuat luka cambukan di tubuhmu
membusuk dan bernanah. Mereka tidak ingin kita
sembuh. Mereka ingin kita mati. Kalau kita mati mereka
bisa menjual organ-organ kita. Kita cuma orang ilegal,
mereka tahu itu, tidak ada yang akan mencari kita.”
Temanmu, Alex, mengikuti pesanmu. Yang sebe-
narnya, adalah pesan napi lain yang kini telah dibe-
baskan.
Sepanjang malam Alex berteriak-teriak. Selama
sebulan dia akan tidur dengan tengkurap dan duduk
dengan cara berjongkok. Cambukan di pantatnya me-
nyobek sejumlah urat dan saraf. Panas dan terbakar.
Dan kalian hanya bisa berharap itu bukan saraf vital.
III
Dia telah membuat kecerobohan paling memalukan
dengan menjual tembakaunya pada sembarangan napi.
Kau padahal sudah curiga.
30__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Menjelang larut, penjaga berkeliling dengan lampu
senter di lorong-lorong yang digelapkan sambil me-
mencet tanda tidur, dan napi itu muncul dari arah barat
tanpa pengawalan, mengatakan perlu tembakau den-
gan sangat. Dia menawar 1000 ringgit lebih tinggi dari
pembeli biasa dan Alex tanpa perhitungan mendalam
mengiyakan. Dia pergi ke toilet portabel di dalam sel,
seperti biasanya, setelah minum air dengan banyak,
kemudian buang hajat.
Di gumpalan hajat akan tersebul buntalan plastik
sebesar kelereng gaco yang bersisi tembakau.
Buntalan itu sengaja ditelan Alex dalam jumlah
sampai empat atau lima bulir. Dia mendapatkannya dari
sipir yang memang mau berkongsi. Tapi anehnya, tidak
seperti sidak kemarin, sipir itu kali ini tidak memberi
tanda bahwa sedang ada inspeksi rahasia.
Padahal kemarin malam dia masih memukul-muku-
lkan kaleng minuman karbonasi sebanyak sembilan
kali dari arah pos jaga di bawah sana; bertanda bahwa
kalian harus menghentikan merokok sebab kepala ru-
tan mencium aroma asap tembakau yang kalian hisap
dan sedang menuju ke sana. Kalian pun akan bergegas
menelan sisa puntung. Kalian membuat rokok itu dari
sejumput tembakau, melintingnya dengan kertas koran
berkas yang disobek dari meja sipir saat keluar apel pagi.
Kau mengerti, tidak boleh ada bacaan apapun di dalam
sel. Kau pernah bertugas menyobek kertas koran dan
menyelipkannya di celana dalam.
Kau ingat, ada titipan dari Mazki, si Bos tahanan dari
Thailand, yakni agar kau menyobek gambar perempuan.
“Dengar, Kas, dunia hanya akan seimbang jika ada
perempuan,” katanya, “maka ketika di penjara terkutuk
Eko Triono __31
ini semuanya laki-laki, perlu ada perempuan, dalam
bentuk apapun itu....”
IV
Jalanan basah, tanah-tanah lengket, paman yang
dikutuki keluarga, karena ia bertato, membawamu ke
pabrik pupuk.
Kalian berjalan 2o kilometer, melewati tiga jem-
batan, dan satu rel kereta api. Di pos pabrik pupuk
paman membelikan nasi bungkus. Kau dengar suara
laut yang mendengkur, kapal-kapal berbagi peluit, truk-
truk besar melenguh, dan lagu dangdut dari radio yang
digantungkan pada dinding.
Tak kurang dari sebulan kau berada di sana. Tak ada
yang mencarimu. Tak ada.
Kau hanyalah manusia asing yang dilahirkan dari
pohon pisang di tepi sungai sebelum banjir menerjang
dan menggelandang ibumu ke laut buat ditenggelam-
kan selama-lamanya. Paman mengajarimu menjadi kuli
panggul pupuk, menguji kekuatan tulang punggung,
otot tangan, dan menicipi perpaduan urea dengan lecet
pada kulit sekitar pundakmu yang baru saja berusia 14
tahun. Seperti semua kuli, kau pun mencoba mengerti;
jangan berharap pada siapapun.
Setahun kemudian, kau diberi kesempatan menjadi
kernek truk pendamping menggantikan kernek lain
yang meninggal dunia karena dibunuh saat malam
lebaran.
Truk adalah kendaraan agung yang selalu bergan-
deng mesra, yang mengirim pupuk dari satu kota ke
kota lain, melintasi pantura, membuatmu mengetahui
sisi lain dari kehidupan para sopir.
32__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Tiga kali kau tertimpa roda truk itu saat meng-
gantinya di jalan dan nyaris mati, sebelum akhirnya
kau belajar bagaimana cara mengendalikan bualatan
besar itu, juga menyopir. Kau sangat bangga. Ada tato di
beberapa tempat. Ada tindik. Juga kalung. Kau menjadi
sopir truk termuda dengan rambut merah dan muka
terbakar. Lima tahun setelahnya kau pulang, meminang
seorang perempuan, dan menikah.
“Kudengar menu pagi ini nasi dengan telor rempah,”
kata Noordin, “pemerintah kita baru saja membayar
upeti.”
V
Kalian berbaris. Seseorang memimpin. Kepala sipir tiba.
Kalian menyanyikan lagu kebangsaan dan hormat pada
bendera di sudut ruang apel pagi.
Dia bicara bahwa Indonesia baru saja mentranfser
biaya hidup tahanan, meskipun hanya sedikit, 1/3 dari
yang seharusnya, namun cukup kiranya untuk mem-
buat kalian pagi itu makan nasi dengan telor rempah
dan teh tarik.
Dan hari-hari berikutnya sama seperti dalam jadwal
ransum; Selasa dengan bubur, Rabu dengan kentang,
Kamis dengan kuah sup, Jumat dengan nasi, Sabtu den-
gan kentang lagi, Minggu dengan ubi, dan Senin dengan
roti gandum. Setelah selesai kerja seperti biasanya,
merawat tanaman, sayuran, ternak dan ini-itu, kau di-
minta mengambil biskuit dalam gudang. Sikapmu yang
baik dan jujur, membuat sipir tertarik. Ini kesempatan
baik. Kau akan selalu memakai sepatu but panjang,
dan dengan jeli menyisipkan gula, susu, atau kopi ke
dalamnya. Tentu dengan memperhatikan sipir jaga
Eko Triono __33
yang cara pandang hidupnya hanyalah kecurigaan dan
rasa waswas. Kau berhasil. Kau bawa roti biskuit keras
itu dengan tenang. Seraya pergi ke dapur dan menyu-
supkan barang-barang curianmu itu.
“Siapa yang menjadi kepala regu dapur, keluar bar-
isan!” Kepala sipir bicara keras.
VI
Tak sampai cambuk. Hanya sejumlah pukulan yang
membuat memar. Dan, setelah itu, seperti yang anggota
sel blok kalian inginkan, kepala dapur diganti.
Dan itu adalah dirimu. Kau berhak mengelola semua
makanan untuk konsumsi napi dan artinya kau tidak
akan kelaparan lagi sebab bisa cumal-cumil. Kelaparan
yang membuatmu harus pergi dua tahun silam men-
inggalkan istri. Istri yang tak tahan melihat sofa baru,
tivi baru, motor baru, dan apa-apa yang baru milik
tetangga. Kau pun mendaftar sebagaimana dua orang
lain dari desamu. Ketika ditanya kenapa tidak jadi sopir
truk gandengan lagi, kau menjawab perempuan mudah
kesepian dan curiga, seperti mata-mata. Dan kau pergi
jadi TKI untuk mendapatkan modal usaha. Kau tidak
sendirian. Ada Rinto Jumadilakir. Kau tidak tahu dimana
si Karso. Berbulan-bulan kerjamu membalak hutan
dalam komando Taiko.
Di tempatmu, di daerah yang tak terindentifikasi
lagi, tertampung orang-orang dari segenap tempat.
Saling berbagi hidup, babi, dan kangkung yang tumbuh
di rawa-rawa, sebelum suatu hari yang tak terduga ter-
jadi dengan setiba-tiba kematian. Hari yang membuat
pembukaan untuk membawamu ke penjara.
“Ada napi baru,” kata Alex padamu sambil terseny-
34__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
um, “lihat nanti, Kas, orang tampan baru akan menyesal
dengan ketampanannya ketika dia berada di penjara.”
Kau ikut senyum, meletakkan beberapa biskuit.
Kau tahu betul betapa beruntungnya menjadi orang
jelek di penjara yang sebenarnya ini, karena bos Mazki
pasti akan memintanya berada satu sel, memijit, dan
melayaninya, jika tidak mau, sejumlah hantaman akan
menghujam perut. Perut tidak kentara bekasnya hingga
sipir seringkali tertipu siapa yang habis dipukuli oleh
siapa, ini rahasianya. Dan napi baru itu berjalan mele-
wati sel kalian yang sejam lagi, saat waktu tidur, akan
terutup secara otomatis. Dia seperti tegang memasuki
lorong sihir yang tak diketahui perlahan kelak bakal
merubahnya menjadi pelacur laki-laki, mengantikan
semua lelaki tampan dan berkulit mulus lain yang
dipenjara di tempat ini.
VII
Seandainya bukan di tengah hutan, tentu telah muncul
di berita televisi pada pukul 6 pagi, atau di koran-koran
kriminal halaman depan; sebuah gambar dari temanmu,
Fajar Sutarno, si Duda paling murung itu, dengan luka
remak di kepala akibat pukulan benda tumpul yang kau
tahu persis adalah besi ungkit milik Kiman.
Darah mengumalkan rambut hitamnya jadi hijau-
hitam. Ada yang mengental, mengantri di lubang tel-
inga kirinya, seolah masih ingin kembali pada jantung.
Yang sayangnya, setengah jam lalu jantung itu telah
menghentikan diri dari denyut-denyut yang tak terukur
seismograf.
Di perutnya ada sisa pembedahan dengan teknik
berantakan, seperti cara seorang istri yang baru belajar
Eko Triono __35
memasak ikan lele untuk sarapan, membedahnya dari
bawah kepala lalu ke arah ekor yang abu-abu. Kiman
memang pernah cerita padamu bahwa duda sombong
itulah yang paling mencurigakan atas hilangnya be-
berapa benda emas hasil tabungannya juga milik be-
berapa kawan lain.
Sebelum polisi datang dan semua akan menjadi
menakutkan, kalian, kau dan Rinto, sempat membolak-
balik tubuh si Duda.
Dari cecaran usus dan lambung yang amburadul di
sekat-sekat diafragma perutnya, kau masih menemu-
kan cincin emas yang tak berkilau tapi memberi tahu
bahwa logam itu memang sungguh mulia kehadiran-
nya. “Seandainya aku memiliki ide ini sebelumnya,”
kau angkat kata dan Rinto tidak menjawabnya kecuali
dengan rasa takut pada penjara, sehingga dia bergegas
pergi ke biliknya, mengemasi barang, sebelum kau
sempat menutup mata si Duda yang seolah menolak
untuk terpejam selamanya. Kau menyimpannya. Kalian
bergegas berlari menembusi ranting dan waktu yang
masih dingin. Kawan-kawan lain masih dibius peri
penidur. Kalian menuju kota, karena kau tahu persis si
Taiko adalah pembenci keledai.
“Taiko tidak mengampuni kesalahan sebanyak dua
kali,” kau menyetop bus, “tapi kemana kita akan pergi?”
Arahpun cuma pasrah yang diselipkan ke dalam
harapan-harapan tanpa nama, tanpa alamat.
Tak lebih dari 3 x 24 jam kau dan Rinto ditangkap
tak jauh dari daerah belanja saat ada inspeksi, sebab
dunia ini hanya menerima orang yang punya kartu
identitas, bukan lagi menerima siapa yang sepenuhnya
bertubuh manusia.
36__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Hewan yang punya identitas resmi jauh lebih sah se-
bagai warga negara, dibanding imigran yang seutuhnya
tercipta sebagai manusia.
Manusia moderen yang diakui jaman ini sebenarnya
tak lebih beda dari hewan-hewan yang memiliki kartu
identitas resmi dengan sederet nomor induk dan tinta
stempel warna-warni. Kartu identitasmu di tangan Taiko.
Dan tak mungkin mengambilnya. Pernah suatu ketika
kalian bermasalah dengan hukum dan Taiko yang menge-
luarkan kalian hanya dalam waktu seminggu setelah ka-
lian dipenjarakan dengan tuduhan mabuk sembarangan.
Tidak ada toleransi untuk kedua kali, Taiko berkata dan
menjelaskan perihal pemotongan gaji kalian. Pada Jumat
malam, kalian berkumpul dan si Duda mengatakan
pada Kiman, bahwa dia terlalu miskin sebagai seorang
pemuda.
“Dia sombong sekali,” Kiman berbisik padamu
sesaat sebelum tidur kembali di bilik barak, “di peran-
tuan ini, kita sama-sama manusia yang diasingkan.
Jangan pernah melukai hati yang lain!”
VIII
Itulah kalimat terkahir yang kau dengar enam jam
sebelum suara minta tolong yang samar dan kau berlari
lalu melihat Kiman menghancurkan tubuh si Duda di
kamar mandi.
Dan kalian tak ingin jadi tersangka atau terlibat
urusan hukum yang memang tak pernah mengun-
tungkan.
“Di mana teman-teman kita sekarang, Rinto?” kini,
kau coba ajak Rinto bercakap-cakap. Seminggu lagi,
Eko Triono __37
kalian sudah genap setahun dalam penjara.
“Mereka mungkin sedang masak babi, Kas. Atau
baru saja melarut semua pancing ikan gabus yang
ditebar sepanjang rawa-rawa, membakarnya, ditaburi
garam, dan—”
“Kamu rindu suara pohon yang ditebang, To? Suara
lenguh gergaji mesin dan bau kayu yang dibelah?” Kau
bersandar pada jeruji, jam sudah bersatu dalam dini.
“Biasanya jam segini kita masih lembur: membelah
gelondongan, menandai balok-balok dengan ukuran
merah—”
“Ya. Kadang-kadang,” Rinto membaring telentang,
kedua tangannya jadi bantal, “Tapi, aku lebih kangen
anak dan istriku, Kas. Sedang apa mereka? Sudah makan
atau belum—”
“Sabar, To, seminggu lagi kita dibebaskan—”
“Dan kita bingung mau kemana—”
“Nah, itu dia,” kau tersadar, “seandainya kita punya
paspor, seandainya, tapi toh punya pun, belum tentu
kita dapat kerja.”
IX
Kau coba tidur tanpa tahu, barangkali, ketika kau
terbangun, ada lagi algojo yang tengah siap dengan
rotan sebab, si Beju dari Vietnam, atau mungkin si
Nadim dari Thailand, telah berbuat kesalahan lagi dengan
menyobek spons kasur tidur buat membersihkan hajat.
Air di sel sering habis hingga toilet portabel adalah
masalah lain.
Dan, seperti yang pernah terjadi, seorang sipir
akan membentak-bentak dengan gaya seekor hewan
38__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
peliharaan yang diikat lehernya dengan kaidah meng-
gonggong, disiplin, dan setia.
Dia meminta mereka merangkak seperti buaya
terbodoh sambil mengingit spons bercelobek kotoran
hajat untuk dibawa keliling gedung penjara sebanyak
lima kali, kemudian ke tempat sampah, dengan mulut
dan hanya dengan mulut mereka yang terhormat.
Kau semakin dalam menyusupi gelapnya kepala
sendiri. Tanpa tahu, barangkali, seminggu lagi, kalian
dibebaskan setelah pesta joged yang meriah melepas
kepergian: semacam perpisahan sentimentil. Joged yang
berarti sejumlah pukulan pada perut dari para sipir yang
membuat kalian bergoyang menggeliat kesakitan dalam
iringan musik yang mendayu.
Setelahnya kalian digiring ke kapal dalam penga-
wasan penuh untuk dikirim ke Batam, pulau terdekat.
Dan barangkali, kalian, yang dari Indonesia, akan
dijemput oleh petugas, atau tidak sama sekali. Akan
diantar ke daerah asal masing-masing, dengan tiket bus
dalam negeri, atau tidak sama sekali.
Tiga hari setelah Batam, barangkali kau akan meli-
hat istrimu menunggu dengan kesetiaan sebatang
pohon jarak, yang dahulu kau semai di pekarangan
cinta dengan kesungguhan seorang lelaki yang bukan
petanam paksa, dan kini tengah tegap menjaga bunga
dan buahmu, menunggu untuk jadi abadi bersama
kehangatan dari kasih sayangmu.
Atau barangkali, ternyata diam-diam dia telah
menikah dengan lelaki lain yang lebih mapan, tanpa
menunggu pesetujuanmu.
Mereka mungkin memiliki buah hati bandel yang
gemar bertapa di bawah talang hujan dan membay-
Eko Triono __39
angkan diri sebagai kesatria yang melawan raksasa,
seperti dalam wayang dan film.
Kau menapak makin jauh melintasi tangga keg-
elapan di kepala sendiri yang berlumut dan dingin;
menuju lorong dan pintu penghilang; menuju ruang
rahasia dari rumah tidur yang sepenuhnya terbuat dari
negasi cahaya, tanpa daun jendela; tanpa kau tahu apa
yang bakal terjadi selanjutnya. Sebab kau, Kas, kau
pun telah lama mengerti bahwa esok akan selamanya
barangkali.[*]
40__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Anak Manis
Anak Manis tengah asyik makan malam bersama
Papa dan Mamanya, saat tiba-tiba ingat, dan, bicara
dengan nada terus terang yang khas anak-anak, “Anak
Manis tahu, Papa itu korupsi, dan kata Bu Guru, Papa
boleh dihukum mati.” Anak Manis mengambil ayam
goreng tepung. Dan Papanya menjadi gelas yang berisi
sirup merah; yang menggelundung tumpah, menetes-
netes di lantai dingin, lalu pecah menggema ke udara,
dan belingnya menancap ke segenap perabotan di
sekelilingnya.[*]
Eko Triono __41
42__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Kenapa Harus Saya
TUKANG KEBUN yang salih bersedih sebab ditangkap
dengan tuduhan aneh. Selasa pukul 08:00 pagi ia
digelandang ke rutan. Padamulanya adalah insomnia-
baru. Kompleks Fur Elite diserang insomnia-baru
yang menular dengan cepat dan mengerikan. Di balik
jeruji besi, ia terus bertanya-tanya, apa kesalahan yang
diperbuatnya, sebagai tukang kebun biasa yang tak
berpendidikan. Sipir membentak. Seorang introgator
yang tadi memeriksa masuk kembali. Masih basah
rambutnya, menggunakan kaos, dan, sepatu bersemir,
tangannya berbatu akik merah delima, dan pendek kata:
tampan sekaligus magis. Si Tukang Kebun bertanya
lagi sebab nyaris tak percaya. Jawabannya hampir
sama, “Kamu telah berdoa yang tidak semestinya.
Penyakit seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa campur
tangan golongan jin, atau, Tuhan. Dan, karena para
dukun menyatakan itu bukan kegiatan jin, maka yang
Eko Triono __43
terakhir adalah jawabannya. Kenapa kamu? Karena kata
penerawang kamu satu-satunya warga di kompleks Fur
Elite yang paling rajin beribadah, dan, jarang melakukan
kesalahan. Oleh karena itu, pastilah kamu telah berdoa
yang tidak pantas, yang membuat Tuhan murka dan
menimpakan kutukan. Dan, itu jelas melanggar hukum,
sebab, doamu telah menyakiti banyak orang, apalagi di
kompleks itu banyak pejabat penting negara. Bahkan
tiga di antaranya, jaksa, polisi lalu lintas, dan pejabat
dirjen pajak, telah mati dengan mata pecah dan
kepala kusut cemrawut. Sampai di sini kamu mengerti
kesalahanmu?” Tukang kebun menggeleng lalu
tertunduk. Dan, jam berganti saat, masuk lagi seorang
introgator lain yang berbeda sikap dan pendapat dengan
introgator pertama. “Virus apa yang kau sebarkan?”
Terbelalak. “Jangan pura-pura bodoh, kau agen rahasia
dari mana?” Melongo. “Sudah, mengaku saja, siapa
rekananmu?” Tak mengerti. Introgator absurd itu kesal.
Ia menjelaskan begini: sejak seminggu hampir semua
penduduk kompleks Fur Elite dilarikan ke rumah
sakit. Gejalanya satu, mereka terserang insomnia-
baru; “insomnia abadi”. Mereka tak bisa tidur barang
sekejap pun. Efeknya, pembuluh mata mereka pecah,
ginjal terserang, jantung terancam, dan organ-organ
dalam yang tak diistirhatkan dalam tempo lama itu
tak ubahnya mesin yang tak henti digunakan. Sampai
aus. Sampai rontok satu persatu. Sampai total mampus.
“Dan kau tetap tak mau mengaku?” “Kenapa harus
saya penyebabnya, Tuan?” “Karena kau satu-satunya
yang masih selamat dari kompleks itu!” Sebab merasa
bicara dengan orang tolol dan rendahan, introgator
itu keluar. Ia berunding dengan rekannya tadi yang
44__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
berbeda praduga. Mereka berdebat. Dan bertengkar
serius. Sampai akhirnya, kembali masuk. “Jelaskan
apa yang sebenarnya telah kamu lakukan?!” Tukang
kebun itu diam. Intogator itu pucat. Agaknya dua hari
tak tidur. Sebuah gebrakan meja. Tukang kebun kaget,
“Baik. Baik. Akan saya katakan. Saya tidak melakukan
apapun.” Hanya itu. Introgator semakin marah! “Kau
telah jelas-jelas membuat penduduk di kompleks para
majikanmu itu tertular insomnia-baru yang mengerikan
dan menyebabkan kematian, masih saja tidak mau
mengaku?!” Prak. Berdarah bibirnya. Tukang kebun
itu tersenyum. “O, merasa hebat, ya, senyam-senyum.”
“Maaf, saya hanya sedang senang hujan sudah turun.
Sejak digelandang ke mari, saya belum menyiram
tanaman, juga, pohon-pohon bayam dalam pot. Istri
saya sangat suka sayur bening. Doa saya terkabul, dan
saya senang sekali.” Introgator yang satu menegaskan
bahwa memang benar dugaannya, semua penyakit
itu karena doa-doa si Tukang Kebun yang mudah
dikabulkan. “Tuan-tuan, saya tidak tau persisnya, saya
hanya kurang nyaman bila mereka serigkali menyetel
musik disko sangat keras dan berpesta, mabuk hingga
pagi hari, sementara saya punya bayi.” “Dan, kamu
berdoa agar mereka insomnia-abadi, begitu?” “Tidak,
saya hanya minta pada Tuhan agar mereka diberi
pengertian atas segala kedzaliman yang telah mereka
lakukan di mana saja.” “Ok. Kalau begitu sudah jelas:
anda yang bersalah dan akan segera diadili.” “Kenapa
harus saya, saya ‘kan hanya berdoa?” “Karena Tuhanmu
tak bisa ditangkap, dihukum, apalagi dipenjara,” jawab
dua introgator itu bebarengan, sepertinya memang telah
biasa mengucapkannya untuk keperluan tertentu.[*]
Eko Triono __45
46__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Perang Kue
I
PAGI INI KARTA LAPAN melihat dunia berisi tikus-
tikus menggairahkan berbalut abu-abu, matanya
menyalakan roh yang lain, dan dia berjalan sangat
malas menggunakan kedua telapak tangan dan lututnya
secara bergantian hingga kuku jemarinya disusupi pasir
hitam, dan orang-orang jadi mengerti: kutukan itu
melanda lagi di desa ini. Desa Palatar yang sunyi: yang
tak dilintasi gugupnya lars sepatu jaman.
Ibunya hilang muka dan menangis-nangiskan diri,
“Percayalah, Karta bukan anak yang tidak hormat pada
leluhur. Ini hanya semacam kecelakaan kecil,” nada
suaranya mencekam.
Orang-orang mengadu gunjing di halaman dengan
menginjak-injak bayangan satu sama lain, bayangan
yang menatap mereka dengan kosong dan hambar.
Kemudian mereka bubar satu persatu membawa per-
Eko Triono __47
tanyaan personal, seperti penonton sulap yang diakhiri
bersambung. Anak-anak itu juga di sana. Mereka mena-
tap nasib temannya dari muka jendela di luar dinding
yang setengah batu bata dan setengah bilik yang juga
menatap mereka dengan penasaran.
Di sela ruji-ruji bambu jendela kamar, mereka
melihat ke dalam: Karta sedang asyik memainkan
seekor cicak sekarat dengan kedua tangannya, lalu dia
berguling-guling, meloncat ke ranjang dengan keseim-
bangan yang menakjubkan, kemudian menerkamnya
lagi dengan cara seekor hewan pemburu hingga bantal
dan selimutnya berantakan. Dia memimpong-mimpong
cicak tanpa ekor itu di tanah dengan tangannya yang ko-
tor sebelum digigit, dilepaskan, kemudian diulanginya
lagi. Mulut dan hidungnya terlihat sesekali mengais-
ngais udara kamar yang lembap. Dan matanya adalah
lup yang terkunci pada satu materi titik fokus.
Dia dipanggil-panggil oleh teman-temannya itu,
“Psst....psstt.... Karta Keriting! Kamu kenapa?”
Karta menatap sumber suara dan mereka segera
berdesakan menyajikan pose muka kehadiran di frame
jendela. Namun, Karta malah mengiau waspada, takut,
dan curiga. Dia bergegas menggigit cicak, bersicepat
merangkak ke bawah ranjang yang gelap, dan mengira
musuh telah tiba. Ibunya yang dikagetkan gaduh mun-
cul dengan berlari dan menangis dari arah pintu sana,
datang menutup jendela, mengaitkan pelatuk, dan tak
henti-hentinya memarahi teman-teman Karta seperti
induk ayam berkaok-kaok penuh emosi kecemasan
pada pagi hari saat langit seakan telah dipenuhi oleh
manuver sejuta elang dan burung gagak hitam, “Pergi,
pergi! Karta sedang berisi roh para leluruh! Pergi sana!”
48__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
II
“SEMALAM KARTA di belakangku,” Pri Kimin bersaksi
sambil berjongkok, “benar-benar di belakangku.”
Mereka membahas peristiwa semalam sambil
merumput di lorong-lorong saf kebun gambas yang
dirambat-rambat pada limas lenjaran galah bambu
hingga menyerupai tenda kemah kecil yang hijau me-
manjang. Tak ada Karta. Tidak seperti biasanya. Aroma
segar kematian gulma dari jenis rumput teki, krokot,
kerma, dan jago-jagoan yang tersabit menjejal; terasa
menyebar lebih kuat dari biasanya bersama lompatan
serangga-serangga mini yang kesal, sebab tergusur
oleh kepentingan spesies dari golongan lain yang lebih
berkuasa. Sesaat kemudian, Genjik Sunarta tampil
mengiyakan kesaksian Pri Kimin dari arah tepi kebun
gambas, bahkan, katanya lebih lanjut, Karta juga mem-
inta kantong plastik darinya. Dan Genjik memberinya
plastik bekas gorengan peyek yang berminyak.
“Mungkin karena kita melintasi rumah San Suwirya,
dan, Karta tidak permisi,” Gendut Sukiman tiba-tiba
melongok dari bawah rambatan gambas, “San Suwirya
punya roh harimau yang muncul setiap malam satu sura.
Aku pernah dengar beberapa orang melihat cahaya mata
tembaga di bawah pohon jambu depan rumah sesepuh
itu bergerak-gerak di malam gelap.”
Mereka lalu saling menimpali dan merasa ngeri,
ngeri yang takjub, takjub yang ngeri.
“Tapi tingkah Karta tidak menyerupai harimau,” Pri
Kimin nampak menghentikan ayunan sabit yang basah,
“dia tidak mengaum dengan mengerikan. Kukira, apa
yang menimpa Karta adalah karena dia tidak berjalan
Eko Triono __49
dengan mudur atau menutup mata saat mengambil
sesaji semalam, seperti kata orang tua....”
“Dan tidak merangkak juga mengiau untuk permisi,”
Genjik terdengar menukasnya dengan nada sahabat
yang menyesal, “dia memang keras kepala! Sekarang
baru tahu rasa.”
Seperti diketahui, tadi malam, seperti malam-
malam pada angka pertama bulan Sura, penduduk Desa
Palatar mengadakan hubungan batin dengan leluhur
di alam kematian. Dengan sebentuk pelita dari minyak
tanah, seperti semua lampu desa ini, dengan lingkar-
lingkar pucuk api yang dicicini warna pelangi cahaya di
atas tampah itu menimpa aneka kue dari semesta dapur
dan bebuahan yang diletakan di sudut depan rumah.
Dan yang paling mencolok selain tampilan pisang
adalah: nasi dari sedulur papat lima pancer. Ini saudara
batin penduduk tropis.
Seorang dukun yang menunggang kuda dan mampu
memanggil hujan akan menjelaskan dengan suara berat:
“Pancer adalah nurani manusia. Dan nasi gunung
berapi menjadi ikon yang metaforik; gunung mungil
nasi putih untuk saudara batin dari arah terbitnya ke-
hidupan, Timur atau Tirtanata, nasi hitam—nasi putih
yang dicampur jelaga—untuk menghubungi saudara
batin di arah Utara atau Warudijaya, nasi merah yang
terbuat dari campuran gula kelapa merah kepada su-
dara batin Selatan atau Purbangkara, dan nasi kuning
campuran kunyit untuk saudara di arah senja, Sinata-
brata atau Barat.” Itulah persaudaraan penduduk Desa
Palatar dengan empat arah mata angin, empat unsur
kehidupan: air, api, tanah, dan udara. Persaudaraan
yang mengagumkan, sunyi, dan abadi.
50__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
“Apa sekarang sudah bisa?” Anak-anak akan ber-
tanya. Tepat ketika mereka diminta duduk melingkar
dan mendiamkan diri dengan terpejam ketika matahari
tenggelam dengan sangat hati-hati.
Semua sesaji telah dipasang. Aroma kemenyan
berpagut. Pelita tugur menjaga diri. Dan hubungan
batin mulai terkoneksi. Roh-roh leluhur turun dalam
bentuk cahaya-cahaya yang selembut debu. Debu yang
bercahaya. Cahaya yang bukan dari panas api dan fos-
for. Cahaya dari cahaya itu sendiri. Roh-roh selembut
debu itu menunggang angin yang juga menjelma kuda-
kuda debu yang bercahaya, turun dari satu beranda
ke beranda yang lain, bersambut salam persaudaraan,
dan bisikan selamat datang dari batin masing-masing
penduduk.
“Apa sekarang sudah bisa?” Anak-anak bertanya lagi.
Dan bila iya telempar sebagai kunci, mereka serempak
membuka malam dengan membawa sesebat kain dan
katong plastik.
Dan entah mengapa mereka bisa keluar secara ber-
samaan dari rumah-rumah yang berbeda, saling ber-
temu dengan kelompok masing-masing seperti serdadu
geriliya yang membawa kunang-kunang dalam botol
sebagai penerang. Anak-anak itu adalah para pengucing:
pengambil sesaji dengan sejumlah peraturan yang rumit
dan mencengangkan. Salah satu peraturan yang paling
sederhana adalah harus belum sunat dan tidak boleh
mengambil di tempat sendiri. Karta bersama kelompok
Genjik, Gendut, dan Pri Kimin. Dan peta pergerakan
serbuan dimulai dari arah utara.
“Kita menghadang pergerakan kelompok Kamso,”
kata Genjik bersiasat. Yang lain terlihat setuju-setuju saja.
Eko Triono __51
III
PADA SERBUAN pertama mereka menuju rumah
terdekat. Pada jarak sekitar dua puluh langkah dari objek
sesaji, Karta masih terlihat memasang penutup kepala
dari selendang, dan, Gendut mengikatnya kuat-kuat.
Genjik dan Pri Kimin juga demikian. Dalam hitungan
lima menit mereka berempat sudah merangkak dengan
cara seekor kucing, dan serempak menuju objek sesaji
dengan mengadu kecepatan, “Ngiau, permisi Mbah,
ngiau, permisi Mbah, ngiau, permisi Mbah....”
Demikian seterusnya suara mereka, sambil men-
gendus-endus untuk memastikan objek dan kue-kue
sesaji yang diambil dengan reraba-reraba sebab mata
ditutup gelap.
Anak-anak itu mengambil apa yang bisa diambil,
pisang, sayur, atau apa saja, asalkan jangan apem dan
tentu nasi sedulur papat, nasi empat saudara batin.
Pemilik sesaji tidak boleh melihat, mereka di dalam
rumah, berpaling, dan ketika ngiau pertama terdengar
mereka harus mempersilahkan. Bagi pengucing yang
tidak membawa penutup mata, mereka harus berja-
lan mundur dan meraba-raba dengan membelakangi.
Sekali saja mereka mengintip, mereka akan berubah
menjadi bertingkah layaknya seekor kucing, sebab bagi
penduduk Desa Palatar hanya kucinglah yang pantas
mencuri, bukan manusia.
Dari satu objek sesaji ke objek yang lain mereka
menyerbu hingga ke rumah yang ke sebelas.
“Dari dulu, tidak ada satupun di antara kita yang
mendapatkan ingkung burung merpati,” Karta meng-
gerutu dan setelah itu menghilang. Ingkung yang di-
maksud adalah burung merpati jantan putih dan utuh
52__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
yang setelah dibersihkan bulunya kemudian diolah
opor dan dimbumbui rempah disajikan bersama sesaji
sebagai hubungan dengan leluruh kelahiran. Dan konon
rasanya membuat yang makan sebahagia seorang ibu
yang melahirkan anak pertama, tentu anak yang dinanti
dan dinginkan kelahirannya.
Tapi mereka selalu gagal. Barangkali anak-anak di
kelompok lain jauh lebih cerdik.
Padahal Karta sangat menginginkannya. Kebahagiaan
baginya datang dalam sesaji tiap satu semester, sura dan
puasa, dengan kue-kue sesaji yang jelas diam-diam
saling dipertandingkan antar keluarga demi memikat
roh-roh leluhur yang menjelma debu cahaya.
Karta cuma tinggal bersama ibu. Ayahnya terkena
penyakit yang membuatnya diasingkan bersama kelom-
pok orang perahu. Ayahnya hidup di sungai sembari
menunggu kesembuhan, berputar, dan berdayung.
Hidup orang-orang terasing itu adalah sungai dan
sungai adalah kehidupan, dan, makan dari ikan yang
dibakar di tepi pantai muara yang berisi kucing dan
orang gila buangan.
Ketika ia diberi tahu tentang Karta yang tertimpa
kutukan leluhur, ia tidak mengerti.
Genjik dari arah tepi sungai bergerak-gerak dengan
kode pada udara. Namun tetap gagal. Dan mereka, Gen-
jik, Gendut, dan Pri Kimin, pulang membawa karung
rumput pada kepala. Sabit mereka berkilat ditimpa ma-
tahari pukul dua yang letaknya miring dan menguapkan
atap-atap seng. “Lihat itu!” Pri Kimin kaget menunjuk
keramaian dan seekor kuda andong yang tertambat di
depan rumah Karta.
Eko Triono __53
IV
ITU KUDA milik seorang dukun dari seberang sungai.
Dukun itu sudah berdiri di depan pintu di antara
orang-orang yang ramai, tangan kanannya memegang
sebentuk ekor kerbau, dan tangan kirinya mengusap-
usap kepala lalu leher karta yang tengah mencakung
seperti seekor kucing kegelian yang mengusap-usapkan
kepalanya ke kaki si Dukun.
Sesekali Karta terlihat menggaruk-garuk pantat,
dan, menjilat-jilat tubuhnya yang berkaos hitam
seakan-akan itu adalah bulu kembang asam. Setelah
berdaham dukun itu ambil suara, “Saudara-saudara
sekalian, satu-satunya cara agar Karta bisa kembali ada-
lah dengan mengadakan perang kue. Perang melawan
sifat buruk yang melanggar, yang mencuri. Syaratnya,
tiap keluarga harus membuat dua puluh satu apem dan
dua puluh satu ketupat juga gunung nasi mungil sedulur
papat lima pancer, dan, besok malam, setiap diantara
kalian harus melempari Karta dengan kue-kue tersebut.
Kalau tidak, desa ini akan tertimpa bencana yang lebih
mengerikan!”
Orang-orang terdiam kemudian dan saling melirik
kemudian bertengkar dengan bayangannya sendiri.
Namun, tidak menunggu lama. Seketika itu juga desa
disibukkan dengan orang-orang yang memanjat pohon
kelapa, janur-janur yang dipatahkan dan dibentuk, dan
tungku-tungku yang menunjukkan pengabdian.
Sementara Genjik dan kawan-kawan menunggui dari
depan pintu kamar Karta, atas permitaan ibunya, dengan
membawakan jangkrik, belalang, cicak, dan tentu tikus
yang dilemparkan ke kamar dan asyik dimain-mainkan
oleh Karta. Ia meloncat, memimpong-mimpong, me-
54__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
nerkam, menggigit, dan membawanya ke bawah ranjang
yang gelap dan lembap. Di meja yang lain, ada ikan-ikan
laut yang dibakar, ada potongan-potongan ayam yang
dibacem, dan beberapa sisa tulang dari sejumlah ingkung
burung dara yang ditaburi rempah gurih. Barangkali itu
obatnya.
“Ini makanlah! Karta menolak semua jenis sayur dan
buah-buahan,” kata ibunya.
Teman-teman Karta melihat apel, salak, mangga,
belimbing, dan mentimun, sementara dia sendiri
bergegas ke dapur, bersama tetangga buat menyiapkan
upacara perang kue: sebuah kurungan ayam tempat
Karta akan didekam dan dilempari, sejumlah kebutuhan
kenduri, dan tak terkira apa lagi yang akan membuatnya
semakin letih dalam kecemasan. Namun ada yang lebih
tak terduga pada malam harinya saat kesibukan me-
muncak. Ketika itu Genjik sedang berburu cicak untuk
Karta di tepi pagar rumah Genjik yang hanya diterangi
kerlip kunang-kunang dalam botol kesayangannya,
Karta tiba-tiba muncul dari lubang kegelapan.
V
GENJIK MAU teriak dan berlari ketakutan. Karta
mencengkram pundak dan membungkam mulut Gen-
jik, “Stt... jangan bikin gaduh.” Genjik semakin meng-
gigil, merapat ke dinding, dan tak percaya Karta telah
tampil dengan berdiri dan berbicara.
“Argh, jangan bodoh begitu! Ini permainan, per-
mainan yang harus segera selesai,” Karta menjelaskan
dengan berbisik, bahwa upacara itu tak boleh terjadi, “aku
tak mau seluruh tubuhku memar.” Genjik menampik
dengan gemetar yang masih, dan, mengatakan bahwa
itu akan menyembuhkannya dari kutukan roh leluhur.
Eko Triono __55
Karta tertawa, “Dasar bodoh, aku ini berpura-pura!
Aku ingin makan ingkung burung dara. Dan kita tidak
pernah mendapatkkannya. Orang-orang tua itu selalu
mengambilnya lebih dulu dari sesaji sebelum kita da-
tang!” “Kamu tidak menutup mata? Kamu tidak ber-
jalan mundur? Kamu....” “Genjiiiikk, mana berani aku
melakukan itu! Aku keluar sebelum kalian keluar dan
melihat apa yang dilakukan orang-orang tua.” “Dukun....
dukun itu? Cicak itu, tikus itu....” “Halah, dia tidak lebih
pandai dari semua tipu muslihatku. Dan kau kira aku
mau makan cicak? Makan tikus? Akan segera kukem-
balikan pada kalian. Semua hewan bau dan menjijikan
itu masih ada di bawah ranjangku yang gelap! Sudah,
sekarang yang penting bagaimana caranya agar perang
kue itu tidak jadi dilakukan. Aku sudah mencuri-curi
melompat lewat jendela dan berharap pada kalian. Di
mana teman-teman yang lain?”[*]
56__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Bukan Aku
yang Membunuhnya
“BUKAN AKU yang membunuhnya. Ia membawa anjing
galak setiap pergi kemanapun. Dan, aku takut anjing.
Jadi mana mungkin aku mendekat-dekat. Kalau
mendekat saja tidak, bagaimana bisa aku membunuhnya
pagi itu? Aku tidak memiliki senapan. Tidak mengerti
bagaimana memperlakukan peluru untuk mencabut
nyawa liyan. Tidak, tidak. Aku tidak bisa teluh. Aku
tidak punya kosakata persekutuan dengan dunia paling
absurd itu. Aku tidak gemar menghafal mantra. Kalau
kalian dapati ada sajak-sajak di buku harianku, itu
hanyalah mantra kesedihan yang kukumpulkan setiap
kali aku patah hati, atau saat aku mengingat kenangan-
kenangan pahit yang telah menjadi bagian perasaan
pribadi. Aku tak mengerti, mengapa cinta selalu
mengajari manusia berpuisi, seolah ada yang ingin
diabadikan dari perasaan sebelum dan sesudahnya. Aku
memang di sana. Tapi bukan yang pertama lihat.
Eko Triono __57
Seorang Tua itu mengkurap beku dekat tong sampah.
Jaketnya terkesiap. Syalnya terserak. Mulutnya menganga
mengeluarkan uap kepagian yang terakhir. Aku tahu.
Ada luka cekik di lehernya. Semacam dua titik dari
gigitan taring ular raksasa. Dan seperti kalian lihat, ada
lingkaran darah di dada kiri. Kukira, itu sisa-sisa kerja
keras sebutir peluru menembus, dan memecah
pembuluh, tapi aku tak yakin jantungnya ikut
tertembak. Aku menjongkok untuk melihat apa ia
masih hidup. Tepat ketika itu Seorang Penjaga Toko
kudengar berlari dari tenggara. Dia berteriak-teriak
dengan gegabah menyebabkan semua orang di
kompleks ini seperti semut digebah-gebah dari
sarangnya. Dengan capit frasa negatif, mulut mereka
ribut, aku pun segera digigiti berjuta tuduhan dalam
satu tema. Aku membela diri, tapi percuma. Tak
berguna pembelaan saat kita berada di dunia jamak
yang sepakat menentang secara bersamaan. Tak ada
yang mau dengar. Seorang Penjaga itu telah meyakinkan
mereka: aku inilah yang membunuh Seorang Tua, yang
selalu membawa anjing kemanapun ia pergi. Karena dia
tahu, aku pernah menceritakan perkara ketakutan ini
padanya, pada Seorang Penjaga Toko itu. Aku memang
takut anjing, tapi itu akan jadi alasan terbodoh bagi
seseorang yang terpelajar sepertiku untuk membunuh
orang lain yang lebih tua sekian dekade. Kuakui, setiap
aku melihat si Kaki Empat berbulu menjijikan, rasanya
seperti berhadapan dengan sederet nasib sial yang
dikabarkan malaikat. Kakiku akan tergigit, tepat di
bagian belakang tulang kering. Celanaku tersobek.
Dagingku tercabik. Darah akan keluar dari pilinan
ototku yang kenyal dan disudet. Ia cakar mata dan
58__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
wajahku. Ia akan mengonggong dengan suara iblis yang
terpendam di ruang bawah tanah selama ribuan tahun.
Lalu tertawa dengan lidah dan liurnya yang busuk. Dan
rasa sakit akan menginfeksi tubuhku, bersama virus
rabies yang akan membuatku menggigilkan kematian
di usia muda, usia yang seharusnya masih dipenuhi
gairah asmara. Aku tidak ingin mati muda. Aku belum
nikah. Belum tahu surga lain. Dan, mati digigit anjing,
bukanlah mati yang elegan. Malah terdengar lucu dan
menyedihkan. Aku ingin mati di usia tua, maksudku
tidak terlalu tua. Terlalu tua membuat seseorang
nampak telah mati sebelum dikuburkan. Aku tidak
tertarik dengan orang terlalu tua yang masih hidup, apalagi
yang banyak bicara untuk mengobati ketakutannya
sendiri menghadapi dunia, menentang kematian.
Dunia yang mengasingkan mereka. Kematian yang
sebenarnya tak lagi peduli dengan cerita mereka. Aku
cenderung kasihan, kasihan yang menjadi benci.
Karena, orang yang terlalu tua, tapi masih hidup, akan
memintaku mendengarkan cerita kehebatannya,
semasa gagah dulu, dengan seolah-olah semuanya baru
terjadi seminggu atau dua bulan yang lalu. Ia akan
bercerita selama berjam-jam, bahwa di musim panas,
ia sekolega berpetualang di hutan untuk berburu rusa
dan seterusnya. Aku diam saja. Meneruskan kerjaku
merapikan tanaman. Ia akan, dan selalu akan seperti
ini, duduk dengan membawa kursi rebah, meminta
pembantunya menyiapkan teh herbal, dan, meja yang
dipenuhi kue yang bersahabat dengan giginya yang
rapuh. Padamulanya, aku akan menghentak-hentakan
gunting tanamanku, agar terdengar keras membising
emosi. Aku ingin beri tanda: bosan. Cerita yang diulang
Eko Triono __59
dan diluang. Tanpa kejutan yang menarik, selain
memang terkesan diimbuhi di sana-sini, tapi itu cukup
kuat untuk memberi tambahan bukti; aku semakin
membencinya. Mungkin ia paham isyarat itu. Aku
sedang tidak bisa diganggu. Sekali dua kali ia pun pergi.
Tapi tidak setelahnya. Seolah ia tak peduli. Aku
mengendarnya atau tidak, sama saja. Selagi di sudut
telingaku tak ada tanda-tanda sumpalan, maka ia terus
bicara dan menceritakan cerita yang sama, bahwa ia
telah menghabiskan banyak kekayaan untuk berburu
dari hutan ke hutan. Hutan-hutan yang jauh dan
tersembunyi. Dengan hewan-hewan liar, semak belukar,
rawa, dan dengan penduduk aslinya yang bodoh, yang
terbelakang. Yang meminum bensin lalu muntah-
muntah dekat api unggun hingga api itu menyambar
ke mulut dan membuat lari ketakutan karena berubah
menjadi manusia naga yang menyembur-nyemburkan
api biru. Ia tertawa terbahak-bahak setiap kali
mengingatnya. Tawa manusia tua yang bangga pernah
jadi biadab. Maka dari itu, aku tak ingin mati terlalu
tua, tua yang tua sekali. Lebih-lebih, harus memelihara
anjing untuk melindungi diri dari serangan orang yang
tidak dinginkan. Aku tak mau, meski aku juga tak mau
memaksa orang lain untuk setuju dengan pendapatku.
Lihat saja Seorang Tua, setiap kali ia bercerita tentang
perburuannya itu di dekatku, anjingnya, yang sebesar
bayi tiga tahun, akan mengendus-endus kaki, seperti
spionase bodoh, hingga tubuhku jadi gemetar dingin,
dan, darah takut mengalir. Aku pun terkencing sedikit.
Ia akan tertawa lagi. Benar-benar tertawa yang
mengejek. Atau mungkin tawa menang. Pipinya yang
kempot semakin berdenyut-denyut menyebalkan.
60__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Sekali dua kali, aku terima, selebihnya, aku katakan
padanya kalau ingin aku jadi pendengarnya, singkirkan
si Kaki Empat keparat itu. Ia menurut. Aku yakin, meski
ia hidup tua dengan kaya raya, tapi kesepiannya
menajam sebab semua anaknya sibuk dengan bisnis,
atau juga perburuan musim panas mereka di hutan-
hutan pedalaman lain. Orang seangkatannya telah mati
semua. Tinggal dia seorang. Tak ada perkumpulan yang
menerimanya lagi. Ia tinggal selilit di geraham kesepian
yang nyaris abadi. Tak ada yang mau dengar ceritanya,
selain aku. Pernah kuusulkan beli robot. Ia marah. Itu
menghina katanya. Baiklah, akupun bersabar jadi
pendengarnya, hingga nanti mulutnya beku, aku
percaya tak lama lagi. Bukan hanya karena ia bos, dan
aku; seorang pekerja taman yang setiap pagi datang dan
sore hari kembali pulang. Lebih dari itu, aku sedang
menyelesaikan studi khusus tentang perbankan di
kota ini, dan, butuh menggali informasi kondisi
perekonomian di era lampau, untuk menyusun
semacam tesis khusus. Disamping itu, aku memang
perlu uang. Tapi sebelum kajian terwujud, ia telah mati
lebih dulu. Jujur, aku senang dia mati. Ingat, aku senang
bukan berarti akulah yang membunuhnya. Tidak, tidak
sama sekali. Bukan aku yang membunuhnya. Aku hanya
senang ia mati. Itu saja. Bukan karena ia akan berhenti
mengoceh selama aku bekerja di taman rumahnya. Aku
malah mulai membayangkan; akan ada yang kurang
saat nanti aku merapikan tanaman. Tanaman yang di
mataku telah jadi manusia klorofil. Kupangkas
pertumbuhannya yang tak perlu dan tak terarah jadi
bentuk tertentu. Tapi aku tak mungkin memotong
batang utamanya, karena itu akan membuatnya layu
Eko Triono __61
kering. Seperti manusia, ada ingatan penting yang harus
tersisa untuk membuatnya tumbuh demi suatu tujuan.
Bukan begitu? Pagi itu aku datang lebih awal. Bukan
karena aku berniat membunuhnya, tidak, tidak sama
sekali. Aku bukan orang yang keji, meski perasaanku
cenderung dingin pada kehidupan. Aku datang pagi,
karena hari itu jadwalku memangkas bunga bougenvil.
Bunga yang juga kesukaan ibuku di daerah asal sana.
Aku tak tega jika harus merapikannya saat matahari
telah terbit dan beberapa ranting, dan bunga, merasa
hari itu masih miliknya. Aku ingin mengendap,
memotong rantingnya yang tak perlu saat embun masih
membius dalam mimpi. Hanya itu. Kalau tak percaya,
lihat saja catatan buku sajakku itu. Di sana ada perihal
bougenvil dan embun pagi. Aku lupa sajak nomor
berapa. Nah, itu pagi aku mengayuh sepeda, aku lihat
aktivitas awan samar yang kukira akan cerah-cerah saja.
Burung-burung gereja meloncat-loncat menegaskan
suasana. Aku hanya tiba-tiba saja kaget yang bukan
main karena mendengar gonggong anjing. Tambah
gemetar jantungku setelah tahu anjing itu terlihat
berlari menyambutku dengan suara marahnya seekor
iblis yang baru terkutuk. Ia dari arah depan, berlari di
bawah sisa cahaya lampu merkuri jalanan. Sepedaku
oleng seketika. Aku loncat. Kuambil tongkat sepanjang
lengan. Semua orang di kompleks ini tahu, aku selalu
pergi membawa tongkat kayu. Mereka sering
mengejekku. Aku tak peduli. Ejekan disebabkan si
Pengejek hanya sok tahu. Mereka tak mengerti
bagaimana gemetarnya melihat anjing, bahkan hanya
mendengar suaranya dari kejauhan, atau hanya sisa
nafas dan langkahnya yang pernah melintas di jalan
62__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
yang kemudian kulalui. Apalagi pagi itu; berhadapan
langsung dalam satu jalan, sekalipun masih jauh
jaraknya. Yang semacam ini sudah sering kubayangkan
segala kemungkinannya. Dan, nyata, tongkat memang
berguna. Aku senang. Hipotesisku tidaklah suatu
kesiasiaan belaka. Aku arahkan. Tiba-tiba aku ingat,
kata orang, kalau ada anjing kita harus jongkok. Agar
anjing itu tak nyerang. Aku pun jongkok. Tongkat tetap
kuacung kokoh. Seperti ini. Tapi anjing itu tetap terlihat
lari dari kejauhan. Bulunya bergejolak seperti ombak
yang mau menenggak muka pantai. Gongongnya
semakin tajam. Tak ada tanda-tanda ia akan berhenti.
Harusnya aku berbalik dan lari kalau saja hari itu bukan
hariku menerima gaji. Seorang Tua tahu, aku hanya
memotong bougenvil di hari ketika aku akan menerima
gaji. Bukan apa-apa, aku hanya mau menghormati ibu
yang kusayangi. Lagi pula, aku sedang butuh uang yang
sangat. Jadilah aku bertahan. Memasang kuda-kuda
dalam jongkok. Tongkatku kian teracung siaga. Seluruh
tanganku gigil. Sementara jantungku seperti meronta
mau keluar, mau larikan diri melompati pagar-pagar.
Di kejauhan, mata anjing itu seperti hanya diarahkan
untuk membidikku seorang. Aku sempat berharap ada
orang-orang pertokoan yang keluar, lalu menolong. Tapi
nihil. Juga pasti akan menimbulkan ejekan nantinya.
Maka biar, kulawan sendiri saja. Dan seperti disengaja
alam, pagi berembun itu hanya buat aku, anjing, dan
burung-burung gereja yang terkesan sedang apatis pada
keadaan. Aku tak ingin mati muda. Kalau sampai anjing
itu benar menujuku, aku harus melawan. Aku sempat
memastikan sebentar ke belakang dan sekeliling. Benar-
benar tak ada orang lain. Aku merasa anjing itu mau
Eko Triono __63
membunuhku di usia muda. Mungkin ia dendam,
karena saat aku motong tanaman sambil mendengarkan
cerita Seorang Tua, ia selalu diikat pada tiang di beranda,
dan hanya berputar-putar yang membosankan di sekitar
tiang. Saat aku berbalik menghadap depan, anjing itu
telah tepat meloncat. Astaga, aku tak mengira secepat
itu datangnya. Ia loncat menerkamku dengan kaki
terbentang. Nafasnya busuk. Gila! Untung aku tidak
mati. Untung, untung. Saat itu kuayunkan tongkat
dengan sembarangan yang bertenaga maksimal dari
bawah ke atas. Aku sudah memejam pasrah; di antara
perpaduan rasa takut dan sisa percobaan melawan. Aku
sempat terkena semprot liur ketika ia menggonggong
kesakitan di udara. Lihat ini. Luka ini bukan hasil
pertarunganku dengan Seorang Tua. Kalian salah. Aku
tak bisa bertarung dalam jarak dekat dan tangan kosong.
Ini adalah cakaran kuku anjing itu saat melompat dan
pukulanku tepat menghantam kepalanya dari arah
rahang bawah, dan ia masih sempat mencakar lengan
kiriku. Hingga baju sobek dan lecet berdarah semacam
ini. Ia terkapar meringkik setelah berdebug di samping
kananku. Matanya nyeri. Kupukul-pukul lagi kepalanya
dengan tongkat sampai kakinya mendendang-nendang
dan berhenti, melemah, mati. Perutnya mengempis-
ngepis tak berdaya. Sebagai seorang yang takut anjing,
aku telah mempelajari kelamahan-kelemahannya untuk
suatu langkah waspada, barangkali juga semacam
ancang dendam. Seperti cara manusia membenci
manusia yang lain. Anjing itu pun benar-benar mati.
Aku sadar, aku dalam kemenangan dan bahaya yang
sekaligus. Seorang Tua pasti marah. Aku akan dipecat.
Mungkin juga akan dibunuhnya. Ia mantan pemburu.
64__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Tidak, tidak. Itu tidak berarti kemudian aku
membunuhnya lebih dulu sebelum ia membunuhku
nantinya. Sudah kubulatkan tekad, aku menyerahkan
kematiannya, yang berarti kebahagiaanku, pada sang
waktu. Biar usia yang menghabisinya dengan cara
terbaik. Aku bukan pengecut. Kubonceng mayat anjing
itu dengan gemetar. Mual rasanya. Ada yang mendesal
dalam lambung. Tapi aku harus melawan rasa jijik demi
hari ini. Hari bougenvil dan gajianku. Ada niat untuk
menguburnya secara rahasia. Dan, aku setuju dengan
niat itu. Kulaju sepeda menuju tempat yang tepat. Saat
itulah, aku mengerem sepeda dengan mendadak. Aku
melihat Seorang Tua telah mengkurap dekat tong
sampah dengan mulut terbuka. Dadanya menandakan
bekas peluru. Dan lehernya, seperti digigit ular besar.
Pertama aku kaget. Selanjutnya aku merasa senang yang
aneh. Senang tidak lantas berarti aku membunuhnya. Aku
senang sang waktu telah bekerja secara profesional
dengan selongsong peluru yang menyot dekat
rumputan. Dan usia, mencekiknya juga. Aku lega.
Benar-benar lega dan bahagia. Itu artinya aku bisa
pulang kampung dengan kabar gembira. Aku akan
menyampaikan pada ibuku, bahwa lelaki pemimpin
rombongan yang dulu pernah berburu di daerah kami
itu telah mati dengan bekas lubang peluru di dada kiri.
Mati menyusul ayahku yang diracuninya dengan bensin
dan api. Mati menyusul orang-orang yang dijadikannya
hewan buruan kemudian direbut tanahnya. Tapi bukan
aku yang membunuhnya. Aku hanya sedang berjongkok
memeriksa denyut ruhnya, saat Seorang Penjaga Toko
berteriak dari tenggara, dan semua orang kemudian
menghambur menangkapku, dan menuduh: aku yang
Eko Triono __65
membunuhnya. Dan, sampai di sini aku yakin aku telah
menceritakan semuanya dengan jujur pada kalian,
dengan apa adanya, tanpa penambahan dan
pengurangan, dari awal sampai akhir. Jadi tolong Tuan
Hakim yang terhormat, lepaskan sekarang dan beri aku
keadilan.”[*]
66__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Menjadi Makhluk Asing
Aku ingin menjadi mahluk asing. Karenanya saat hari
yang kutunggu tiba dengan bijaksana dan dipenuhi
cahaya kebangkitan sang penyelamat dunia, aku
keluar dengan cara seekor jaguar Borges yang baru
saja dibebaskan dari penjara Naskah Tuhan, sebelum
kemudian mengajak kenalan orang-orang yang biasa
kutemui pada hari-hari sebelumnya; pemilik kontrakan
yang selalu bangun jam empat pagi dan tidur pada jam
dua belas malam, sehingga hidupnya telihat begitu
efektif sebagai pemilik toko kelontong; pekerja burjo—
suatu kedai 24 jam, seluruh detik-detik hidup mereka
nyaris dihabiskan dengan menyobek plastik makanan
instan, mengaduk dan mencuci gelas, membuat aneka
jenis nasi, serta memecahkan es batu dan menghitung
jumlah kembalian dengan teliti—aku kadang berfikir
apakah mereka tahu bahwa sekarang telah hari Rabu
dan bulan September pekan kedua? Kuulurkan tangan.
Eko Triono __67
Kukenalkan bahwa namaku adalah San Seroke. Mereka
tertawa. Aku kecut. Mereka menanyakan mau makan
apa? Aku bertanya, makanan apa saja yang ada di sini?
Tidak hanya itu, aku bahkan menanyakan kembali hal-
hal yang harusnya bertahun-tahun lalu kutanyakan,
tentang nama-nama mereka, asal-usul, dan darimana
mereka menyetok barang dagangan, dan bagaimana
bisa mereka hidup hanya dengan pemandangan depan
kedai. Pindah dari situ, aku bertemu teman sebelah
kamarku, dan aku bertanya padanya, daerah apa ini?
Dia kaget dan berlalu. Di tempat fotokopi, aku duduk.
Mereka memanggil-manggil namaku yang lama. Aku
cuek saja. Itu bukan panggilan untukku. Mereka marah.
Kukatakan: namaku San Seroke! Aku sebentuk hidup
baru. Aku bertanya pada mereka tentang kesibukan
dan nama-nama di daerah yang telah bertahun-tahun
kutinggali ini. Mereka tertawa dengan begitu keras;
sehingga kertas-kertas terlempar ke udara; otot perut
dan gigi mereka bergemeletuk seperti roda tank perang;
gelas-gelas kopi retak kemudian pecah di lantai; dan
sekaleng lem tertumbuk di kepalaku, merekatkan
zat di dalam nama dan peristiwa hidupku yang telah
lama mereka kenal—dan betapa membosankan.
Lalu, seorang yang kukenal bijak, lewat. Aku bertanya,
bagaimana caranya agar aku bisa menjadi sebentuk hidup
baru? Ia diam. Ia tidak berkata—sepatah katapun, hanya
menunjuk dua tukang parkir, di bawah pohon waru,
yang sedang sibuk merapikan bidak-bidak catur ke
dalam kotak, sisa jaga semalam suntuk.[*]
68__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Agama Pohon-pohon
Sebelum kau bertanya, “Agama apa yang pantas bagi
pohon-pohon?” hujan lebih dahulu berwarna tembaga.
Merkuri yang tinggi, tegak dan melengkung; ber-
baris menundukkan kepala di sisi jalan provinsi J.,
dan kita mengira mereka sedang sibuk, atau mungkin
berkabung, pada lalu lintas yang senantiasa bergegas,
seperti saat, seperti waktu (yang kerap terlepas dan
bersambung). Penerangan dalam bus dimatikan, sejak
beberapa jam yang lalu.
Penumpang yang lain sepenuhnya mengantuk;
nyaris terlelap, punah dari jaga seolah mereka akan
tinggal di bus ini untuk selama-lamanya. Lelehan hujan
yang mengalir pada jendela kaca jatuh lebih nyata dari
yang semestinya. Dan, entah mengapa, tiba-tiba kita
saling bertanya: benarkah di suatu kota, hujan dan
gerimis dapat berubah menjadi logam? Dan hari akan
bercadar, dan, kita benar akan sampai?1
Eko Triono __69
Kau senyum tipis: jadi logam mulia, atau, logam
hina?
Aku mengangkat bahu.
Itu bukan soal.
Kita saling meletakan pandangan di dalam perasaan
masing-masing.
Dan di luar, cuaca saat ini adalah kabut dalam lan-
skap gelap rawa-rawa pantai. Ada pula nuansa kota-kota
yang kita lintasi; lapak-lapak tenda dengan lampu neon
15 watt, tempat isi ulang pulsa, ATM, penjual buah,
rumah-rumah dengan beranda, restoran, apotek 24
jam, gambar-gambar kangen di bak truk, pasangan yang
saling berbonceng dengan lambat, dan itu, sepotong bu-
lan biskuit yang selalu terlambat 4 menit; bergelantung
pada kemiringan 300 di arah Timur.
Dan kau mulai bercerita soal bulan. (Cerita yang
tidak kusukai karena alasan pribadi).
Bahwasanya, pada suatu malam yang ceria, hari
Sabtu, kalian pernah duduk-duduk di halaman rumah
kontrakan. Zafin, putra kecil kalian, begitu mengge-
maskan. (Aku membayangkan bentuk muka, pakaian,
dan gaya sisiran rambutnya). Dan, katamu kemudian,
sepotong bulan biskuit, muncul dari semak-semak
nyiur, dari arah sungai yang tersembunyi arusnya.
Zafin terpesona melihatnya. Ia kemudian bilang:
“Mama, mengapa malam-malam begini ada mata-
hari?”
“Itu bukan matahari, sayang,” katamu (disertai se-
nyum ingatan geli), “itu bulan.”
“Dan kamu tahu? Zafin memandang penuh
takjub, tak henti-henti, hingga seluruh sinar bulan itu
menggenang di air mukanya. Dan tak kusangka me-
70__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
mang, ternyata, ia baru pertama kali lihat yang namanya
bulan. Ia pun bertanya lagi, ‘Itu bulan siapa, Ma?’ Kami
sempat bingung. Kujawab saja, itu bulan kepunyaan
Tuhan, sayang. Dan ia malah lanjut bertanya, ‘Tuhan?
Siapa dia? Kakek-kakek nelayan ya? Mengapa dia me-
naruh bulannya di sana? Rumahnya di seberang sungai
ya, Ma? Kita main ke sana yuk! Kita pinjam bulannya,
buat dipasang di kamar Zafin.’ Kami terdiam. Antara
lucu dan tak mengerti isi pikiran Zafin. Untung ada
penjual molen lewat. Zafin suka molen pisang. Dan
pertanyaan tadi, ia abaikan dalam seketika.”
Aku minta ijin padamu untuk merasa gembira,
tepuk tangan, dan berkata, bahwa barangkali, putramu
itu akan menjadi seorang filsuf, atau, penyair.
(Meski sebenarnya aku muak dengan kebahagiaan
kalian, dan, benci mengatakan pujian palsu).
Kusebut-sebut perihal mukjizat yang seringkali
terabaikan, teralihkan oleh dorongan menjadi ideal
yang lain. Kau menanggapi dengan baik. Malahan,
kau menyinggung-nyinggung tentang seorang penyair,
yang karena patah hati, lalu memilih jadi relawan di
daerah konflik. Dia berpindah dari satu tempat ke tem-
pat yang lain. Di sana, kata dia, hujan malah berubah
jadi peluru. Tajam dan seringkali berdarah. Kelaparan,
pengungsi, kemah-kemah penuh penyakit, mi instan,
dan seterusnya.
Dia masih muda, tapi sayang, cinta yang gagal mem-
buatnya lebih menderita 10 tahun dari usia kebahagiaan
yang seharusnya dia miliki. Hari-harinya adalah menulis
laporan pembantaian, tinggal di antara orang-orang
yang tak lagi paham apa arti merdeka dan tanah air,
menghibur seorang ibu yang anaknya ditembus peluru,
Eko Triono __71
bernyanyi bagi anak-anak yang kehilangan ayahnya,
meneplok nyamuk yang begitu banyak di malam gelap
musim hujan, dan seterusnya.
Aku buru-buru menambahkan, “Dan dia selalu
merindukan cintanya yang hilang, menulis sajak yang
dirahasiakan, dan, menyusun surat cinta yang tak per-
nah dikirimkan.”
Kau senyum meledek:
“Lalu dia mencoba pulang, entah untuk alasan apa.”
(Kau ini, memang paling bisa).
Dia pulang untuk sesuatu yang masih dirahasiakan,
kataku.
Kemudian, dia bertemu dengan cintanya yang mem-
buat menderita itu, yang telah memiliki anak dan rajin
bercerita tentang anaknya. Mulai dari ketika dia belajar
memanggil ayahnya dengan cadel, sampai soal menye-
but bulan sebagai matahari yang datang di malam hari,
dan, ingin memindahkannya ke kamar—tentu dengan
kemiringan yang sama, 300 dari arah Timur. Mereka
berusaha bercakap-cakap seolah tak pernah ada apa-
apa; tak pernah mengenali satu sama lain, tak pernah
menyentuh satu sama lain.
“Apa pertemuan itu suatu kebetulan?”
Salah satu pertanyaan darinya.
“Kebetulan? Apa itu kebetulan?” Kata si penyair. “An-
gka dalam lotre murahan yang dijagai lelaki tua di tepi
jalan, atau, saat tiba-tiba kita ada dan tiba-tiba tiada?”
“Sayang sekali, sudah tak ada lagi tempat bagimu
untuk menyimpan puisi-puisi. Dunia sudah sesak,
sudah penuh.”
“Dan sudah menyakitkan bagi perempuan yang baru
dicerai; dihapus dari kalimat cinta fiktif.”
72__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Kita diam.
Dendam silih dalam jam digital berwarna merah
saga, di dekat kondektur, saling sulih dengan dingin.
Aku menyandarkan punggung, lelah.
Dan kita memang sudah lama tak menyenangkan
lagi. Cahaya-cahaya saling berpapas dan melewati.
Jalanan berlorong. Berlabirin. Kita seperti melaju dalam
pori-pori terumbu karang. Lagu-lagu lambat diayunkan
membuat penumpang lain makin lelap. Kita hanya
mampu menahan tawa, saat lirik dari Queen seperti
sengaja dilemparkan oleh kondektur pada kita: “Too
much love, will kill you.....” Kita, pada hari yang telah
jadi silam, sebenarnya pernah seperti saat ini. Bedanya,
ketika itu kau bersandar di bahuku, dan, kadang kau
diam-diam mencuri waktu untuk mencium pipiku dan
mengatakan:
“Senyummu terlalu manis untuk seorang pemikir
yang berlagak serius,” (matamu menggoda).
Dan kita mengisi perjalanan dengan menerka apa-
apa yang terjadi di antara rumah pada tepian jalan yang
kita lintasi.
“Kamu tahu, anak itu bilang pada ayahnya: Ayah
mengapa gula-gula kapas berwarna merah muda?”
Ayahnya bilang, katamu selanjutnya, “Itu karena
pedagangnya ingin punya anak perempuan yang cantik,
yang punya leher indah.”
“Bukan begitu,” aku merasa tidak setuju, “anak itu
justru berkata: Ayah, jangan biarkan akau menjadi de-
wasa. Kemudian dilahapnya gula-gula kapas itu sambil
berdoa agar ia tak lekas menjadi besar. Lihatlah....”
Kau tertawa, mana ada anak kecil secerdas itu.
Anggap saja dia pernah mendengar cerita betapa men-
Eko Triono __73
yakitkannya menjadi dewasa; terbatas dari kebebasan
melakukan apapun, menanyakan apapun.
Kau menatapku, benarkah kita telah menjadi de-
wasa? Aku mengangguk. Kita berpelukan. Ada jeda dari
musim yang tak mampu kita tahan. Dan kita berganti
dari memperhatikan seorang anak dalam gendongan
pundak ayahnya, yang sambil menikmati gula-gula
kapas merah muda itu, ke seorang nenek keriput yang
menjemur padi, dan bukit-bukit.
“Menurutmu, apa yang dikatakan bukit-bukit itu
kepada kita?”
Kali itu, giliran aku yang menggodamu, “Beri aku
sebuah tanda, kata sang bukit. Beri aku.... sebuah tahi
lalat. Sebuah, atau lebih.”
Kau mencubitku, geli.
Kita saling melirik.
“Kalau pohon-pohon itu?”
“Menurutmu?”
“Mmm, apa ya, mungkin, mereka bilang, kalian bisa
pergi-pergi, sementara kami, sejak lahir sampai mati
berada di sini.”
Kita mengambil waktu untuk memperhatikan
mereka. Daun-daunnya bersorak sepi di dekat perlin-
tasan. Entah untuk apa mereka ada, jika tak seorang
pun mengakui. Setelah itu, seberapa jarak dari hitungan
bulan, kita tak pernah bertemu lagi.
Selain pertanyaanmu yang tiba-tiba melompat:
“Agama apa yang pantas bagi pohon-pohon?”
“Kenapa memangnya?”
“Bukankah berbagai pohon dapat tumbuh di tempat
yang sama dengan damai?”
“Ya. Kenapa?”
74__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
“Ini soal perasaan. Kau tidak akan mengerti.”
Jujur, aku tak tahu harus komentar apa. Kuren-
dahkan sandaran 15 0 dan mencoba berpikir pada
kursi nomor 11, di sebelahmu ini. Hujan pun semakin
menembaga.
Dan lampu-lampu lalu lintas memberi tahu lagi,
pernikahan kalian memang berbeda agama. Kemudian,
berpisah. Zafin dibawa oleh ayahnya.
Bus berhenti sejenak di kota G.
“Aku mengira, seandainya pohon-pohon beragama,
hewan-hewan berideologi, dan para jin dan tuyul mem-
buat undang-undang dan mengendalikan kekuasan,
hukum, dan juga politik, masihkah kita disebut sebagai
manusia?”
Seorang penumpang naik.
Perempuan, tapi tidak sepertimu. Dia mendekat,
melihat sana-sini kursi yang kosong.
“Boleh aku duduk di samping Anda?”
“Ini sudah kubeli.”
“Tapi itu kosong?”
“Tidak bolehkah aku membeli sebuah kursi kosong
di sisiku?”
“Untuk apa?”
“Ini soal perasaan. Kau tidak akan mengerti.”
“Anda pasti bercanda,” dia senyum, seolah tak per-
caya. Kutunjukan tiketnya: atas namamu.
“Masih tak percaya?”
Dan dia pun berlalu, duduk di sebelah kakek-kakek
tua, jauh dari tempatku berada.
Eko Triono __75
Catatan:
1. Pertanyaan (yang sebenarnya tak perlu) buat baris puisi
Goenawan Mohamad, Di Kota Itu, Kata Orang, Gerimis Telah
Jadi Logam)
76__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Aku Ini Ibumu
“NGOMONG APA kamu tadi ngomong apa hah aku
ini ibu ibumu ibu yang melahirkanmu dengan susah
payah tega-teganya kamu ngomong begitu tega kamu
pikir aku ini apaan aku bangun pagi saat orang lain
masih tidur nyuci baju masak ngepel nyuci pakaian
njemur lihat lihat tetangga lain lihat ada yang seperti
aku ini uang belanja pas-pasan malah kadang dipotong
dihutang aku cari sendiri jualan ini itu ada nggak
tetangga lain yang seperti ini cerewet cerewet ya cerewet
kuwalat kamu kuwalat dasar anak durhaka pingsan
sana pingsan di sumur atau mati sekalian tahu gitu tak
perlu aku lahirkan kamu ke dunia mending dipencet
saat masih dalam kandungan ngerti nggak kamu berat
berat rasanya orang hamil sembilan bulan ngandut
sana-sini mau tidur susah mau makan susah mau jalan
berat sudah gitu kamu tahu saat hamil adikmu malah
ayahmu pergi kencan dengan tetangga sebelah sadar
Eko Triono __77
sadar jadi anak sadar biar nggak kuwalat sudah sukur
kamu tidak kupencet sudah sukur kamu tidak kubuang
ke kali sengsara dikit aja ngeluh coba banyangkan ibumu
waktu kecil subuh bangun masak nganter kiriman nasi
ke sawah beri makan angsa berangkat sekolah mencari
kayu bakar dan tak pernah makan enak sekarang cuma
gara-gara itu kamu tutup telinga dan mau pingsan
di sumur cengep-cengep mau mati banting apa saja
silahkan mati mati kamu mati biar hidupku tenang
buat apa anak sepertimu menyesal aku membiarkanmu
hidup dan lahir kenapa tidak kupencet saja waktu
masih dalam kandungan yang namanya kamu memang
seperti itu seenaknya pulang piring berantakan lantai
kotor baju kotor makanan habis belum lagi masak sana
ikut orang lain saja jadi anaknya orang lain kalau mau
seperti itu tega kamu tega banting pintu dan ngomong
cerwet pada ibumu ibu yang membiarkan kamu lahir
tahu gitu sudah kupencet kamu dalam kandungan biar
nggak lahir biar nggak....” [*]
78__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Pasangan
D adalah seorang pesulap terkenal yang belum lama ini
menikah. Istrinya bernama Z sudah hamil tua. Dengan
terus terang, “Kalau memang kalian memaksa, baiklah,
akan kukatakan. Yang tidak kusukai, dalam tanda petik,
dari Z sebagai istri adalah dia terlalu apa ya, terlalu lurus
dan realis cara berpikirnya,” D mengatakan di acara sapa
selebriti TV yang mengangkat tema tentang hal-hal yang
tidak disukai dari pasangan Anda, dan penggemarnya
menyebarkan ke twitter, ke facebook, dan menggungah
videonya ke youtube, dan media lainnya. Istrinya tak
peduli dengan itu. Dalam keyataannya memang Z,
karena D terlalu sibuk dengan pekerjaannya menyulap
kotak kosong menjadi berisi burung merpati, tisu
menjadi selembar uang, atau menebak angka kartu;
maka dia sering menghabiskan hari, bahkan makan
malam—yang ketika pacaran selalu bersama-sama—,
dengan seekor kucing feral berbulu kembang asam
Eko Triono __79
pemberian D ketika mereka berkunjung ke Baltimore.
“Pulanglah, perutku mau pecah!” Tak lama, mereka
telah berada di rumah sakit. D gelisah yang bahagia
karena beberapa detik lagi dia akan menjadi ayah.
Sebuah jeritan terdengar. Dokter keluar dengan gugup.
Tanpa kata-kata. D masuk dengan cekatan. Beberapa
perawat menepi di dinding seperti beberapa serangga
raksasa yang ketakutan kerena mau disemprot baygon
pembunuh. Istrinya duduk dengan tenang di ranjang.
D mendekatkan langkah, dan terhenyak saat melihat
seekor kucing kembang asam sedang menyusu, dengan
sesekali mengiau manja dalam gendongan istrinya
yang dengan pelan berkata kepada D, “Kau membuat
kenyataan menjadi sihir, dan lihatlah aku adalah
pasangan untukmu; aku membuat sihir menjadi
kenyataan.”[*]
80__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Jam
SEORANG PELACUR dengan dada telanjang yang
bentol-bentol merah membuka jendela di lantai dua;
melemparkan sisa anggur yang bercampur liur seorang
pelanggannya.
Seperti pagi yang kemarin—yang selalu mirip den-
gan pagi yang lain—buangannya disengaja untuk men-
genai tubuh juga muka gelandangan yang ngringkuk di
emperan gedung bordil tua dengan kedingingan. Kali
ini tepat menimpa bibir, hidung, dan mata gelandangan,
yang seandainya dia tahu, dia akan mati hari ini.
Dia membuka mata dengan kaget, bangun seperti
kadal, dan tiba-tiba tersenyum: “Tidak salah aku me-
milih tempat ini.”
Tangannya mencuci muka; kemudian dijilat-jilat
dengan lidah pucat yang rakus, kelaparan. Gang ini ada-
lah sarang paling nyaman bagi gelandangan seperti dia.
Kalau malam seperti altar pesta, dengan riuh, musik,
Eko Triono __81
lampu dan mobil-mobil yang mengerem. Mulai pagi
sampai sore tersulap jadi kota hantu—dengan bau mun-
tahan yang lembab dan mendistribusikan keheningan.
Dia, yang akan mati hari ini, berjalan seperti bayi.
Langkahnya perbaduan antara rasa lapar, malas, dan
ngantuk—seakan telah jadi zombi. Tapi, dia musti ke
depan. Jalan besar pertokoan ada di sana. Kalau bukan
kerjaan, toh mungkin ada makanan. Toko-toko grosiran
buka pagi. Pukul delapan mereka sudah sibuk. Dia pikir
otak pedagang sebagiannya adalah otak ayam; kalau
pun dikurung, mereka tahu kapan waktunya untuk
berkokok.
Dia meludah yang cepat. Tidak lancar.
Menggelantung di bibir. Jadi lendir. Dia haus.
Suara tangan bertepuk. Dia menoleh seperti kura-
kura. “Heh, sini!” Bos toko jam memanggil. “Kau pengen
makan ‘kan?” Jelas ini kalimat hinaan, bukan pertan-
yaan. Dia diam, melirik tajam seperti seekor ular di sela
batuan goa yang bertahan antara waspada, harap, dan
harga diri yang licin.
“Jangan curiga seperti itu,” nada bos ini kelihatannya
baik, rendah, penuh simpatik.
Dia pun mendekat dengan langkah yang dibuat-buat
biasa saja. Bau tubuhnya jelas seburuk pakaiannya. Na-
mun, bos itu agaknya tidak terusik, apalagi jijik.
“Bekerjalah di sini. Kami memerlukan pekerja
tambahan dan juru hitung,”—bos itu memeragakan
kalkulasi—”kau butuh makan ‘kan? Butuh kerja?”—
sepertinya bos itu menganggap dia kelewat dungu
sehingga nada bicaranya berbubah seolah guru sekolah
dasar, atau mungkin karena dia diam seolah patung kotor,
diam karena biasa dilecehkan sebelumnya, dikerjai yang
82__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
menyakitkan—”jangan khawatir, aku akan mengajarimu,
dan menggajimu dengan pantas. Sekarang, ikut aku
masuk! Hei, jangan melompong begitu.”
Dia, yang tidak tahu kalau akan mati hari ini, merasa
memiliki ruh baru hari ini yang ditiupkan dari mulut
sang bos. Dia akan kerja. Akan jadi normal!
Tukang parkir dan penjaga lain, melihatnya dengan
iri yang sinis, jahat, dan tak percaya keberuntungan itu
benar-benar terjadi pada dia yang hanya gelandangan.
SELANG SATU jam, dia keluar. Sudah rapi. Telah
bercukur. Bersisir belah tengah. Wangi. Kemejanya
digulung setengah lengan. Putih. Dengan satu saku di
dada kiri. Dia pun diperkenalkan. Padamulanya, agak
canggung, namun kebahagiaan yang nyata membuatnya
terbiasa.
Di balik semua itu, dia siap bekerja, siap mengabdi
dengan sepenuh hati; patuh dan taat.
Pekerja yang telah lama, sopir sang bos, tiba-tiba
mendekat, berbicara ke telinga—seperti adegan pem-
bisik telinga raja, “Apa bos yakin akan menjadikan
gelandangan ini pekerja? Si dungu yang hanya akan
membuat kerugian dan berantakan?”
“Aku harus berbuat baik kepada sebanyak mungkin
orang,” bos yang memang memiliki banyak usaha ini bicara
dengan santai. Toko grosir jam terbesar di kota ini hanya
salah usahnya, yang bahkan terbilang sangat kecil.
Tukang parkir, yang sedari tadi menyimak pun, ikut
tergerak mendekat, bersandar ke etalase kaca, “Tapi dia
benar-benar dungu. Kenapa tidak yang lain?”
Yang dimaksud yang lain oleh tukang parkir itu,
Eko Triono __83
pasti dirinya sendiri, cara ujarnya begitu jelas.
Bos tersenyum. Dia memanggil gelandangan yang
kini telah rapi, memintanya untuk mendekat.
“Kalian pikir, kalian lebih pandai dari dia, hemh?”—
bos terlihat menantang, ia menunjuk sekeliling—”coba
tunjukan padaku bagaimana cara mengkalkulasi semua
ini? Kamu?” bos mengarahkan kata tantangannya pada
si sopir. Si sopir menggeleng malu dan menatap ujung
sepatunya. “Atau kamu?” kali ini bos menunjuk si tukang
parkir yang terlihat gusar.
“Kuakui aku tak bisa. Karena bos tidak pernah men-
gajariku, meski aku sudah bekerja di sini sangat lama,”
dari cara ucapnya, serta mimik mukanya, dia jengkel.
“Kalau begitu,” kata bos, “aku lebih tahu apa yang
kulakukan daripada kalian. Kalau masih mau bekerja
untukku, kerja yang bener dan jangan ngrasa pinter,
ngerti?!”
Kerja pada tiga jam pertama, dia, yang belum tahu
akan mati pada hari ini, merasa lelah karena kurang
bantuan.
Entah bagaimana caranya bos benar-benar pandai
menggaet pelanggan seperti magnet. Ada saja pesanan
atau yang datang. Dia butuh bantuan. Dan bos, memin-
dahkan seorang pekerja di toko grosir kain yang berada
dekat jalan utama, setengah jam kemudian.
“Ingat, dagangan kita laris, tapi jangan sekali-kali
kalian mengambil. Terutama ini. Apalagi menjualnya.
Kalau sampai ini terjadi, jangan tanya akibatnya.”
Dia mengerti. Dan, padamulanya tidak tertarik.
Namun, takdir seperti hukum gravitasi, ia harus mati
hari ini.
84__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
KETIKA MEREKA makan siang, kepastian itu seperti
menyusup dari celah aspal atau mungkin lobang got.
Atau dari bibir tukang parkir yang menjelma kotak pos
berisi surat cobaan.
Dia mendekat dan setelah basa-basi pada keduanya,
dia mulai menyinggung-nyinggung tengan orang ke-
percayaan bos. Tentu dirinya masuk singgungan itu,
karena telah lama bekerja pada bos, meski sebagai
tukang parkir.
“Dan bos itu sebenarnya... pelit,” tukang parkir
melancarkan serangan. “Kalau tidak, tentu aku sudah
diangkatnya jadi asisten atau bahkan menejer di salah
satu tokonya.”
Dia, yang akan mati hari ini, menyanggah dengan
sopan; bahwa bos itu baik, buktinya, memberikan
pekerjaan. Tidak ada yang lebih baik, selain mereka
yang memberi pekerjaan.
“Itu sekarang. Tidak lama lagi kalian akan di...
phak”—tukang parkir memeragakan orang nendang—
”lalu diganti dengan gelandangan yang lain,” matanya
menunjuk orang yang mengorek sampah, lalu beralih
pada yang sedang meminta-minta dengan merendah-
kan diri serendah-rendahnya demi receh.
Sadar sedang dikelabuhi, dia, yang akan mati hari
ini, segera kembali kerja dengan seksama.
Dia mengingatkan pada si perempuan. Tapi, tidak
digubris. Ya, sudah. Tukang parkir itu kelihatan senang
seperti pancuran yang dapat ember tampung.
“Aku tahu kau mencintainya,” tukar parkir itu bisik-
bisik. Perempuan itu kaget, malu.
Lalu, “Kau bisa berkeluarga bersamanya hanya den-
gan menjual jam tangan emas itu.”
Eko Triono __85
Lebih lanjut, tukar parkir menjelaskan; harga emas
sedang di level tertinggi.
“Kenapa tidak kau sendiri yang melakukannya, lalu
bawa pergi dan selamatkan hidupmu?”
“Dengar, aku sangat dikenali di daerah sini. Ru-
mahku juga tak jauh dari sini; ada anak, ada istri. Jelas,
itu akan menyulitkanku. Kalian? Bebas. Mau lari ke
mana pun, lalu tinggal di mana pun. Aku hanya bu-
tuh sedikit... hanya sedikit komisi,”—dia menjentik
jari kelingking—”dan aku akan bersaksi bahwa kalian
dirampok.”
Tukang parkir itu memintanya untuk menjelaskan
pada dia, yang akan mati hari ini, tentu dengan penje-
lasan cinta juga.
PEREMPUAN ITU menurut, “Kumohon, ambillah jam
tangan emas itu, jual, lalu kita kabur, menikah, kaya
raya dan bahagia selamanya. Demi Tuhan, aku sangat
mencintai—menginginkanmu.”
“Secepat ini?” dia tidak percaya, karena hanya baru
beberapa jam saja. Ini ganjil.
Perempuan itu gemetar, rona mukanya memerah,
dan tangannya menahan perut yang mulai kram karena
birahi melonjak dahsyat seketika, “Bahkan sebenarnya,
bisa lebih cepat dari ini. Sudahlah, cinta bukan hanya
soal kecepatan, tapi... ketepatan.”
Perempuan itu mendekatkan muka, setengah
mendesah, nyaris bersentuhan. Tangan mereka saling
menggapai. Sejenak, ada situasi rumit, sebelum dilepas-
kan dari himpit.
Dengan dorongan kuat menjadi kaya raya—disertai
86__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
gariah hormonal yang telah lama tertekan—dia meny-
erah. Kemudian ketiganya, dengan keputusan dan cara
yang mengejutkan, bekerja sama untuk mengambil jam
emas di dalam kotak khusus. Dan, dasar cerdas, mereka
bersorak menang; berhasil sempurna.
“Sekarang,” atur tukang parkir, “kau pergi panggil
bos di butik depan,”—dia menunjuk si perempuan, dan
seakan tahu perisi bahwa jam menjelang sore begini bos
ada di sana—”lalu kau, lari cari bantuan, bilang tokomu
di rampok, sementara aku akan kondisikan seoalah
di sini baru saja ada perampokan; akan kupecahkan
ini-itu dan seterusnya. Lalu jam emas itu, kau simpan
baik-baik, ya.”
Dalam hitungan tiga, semua bergerak. Bunyi gaduh
diciptakan. Dia, yang akan mati hari ini, berlari minta
tolong bilang ada perampokan.
Beberapa orang, karena sepi di situ kalau siang,
muncul dengan malas. Juga terlihat pelacur yang men-
gantuk. Mereka berjalan, dengan tidak terlalu terburu-
buru, menuju toko jam.
Belum juga sampai, arus beberapa orang datang dari
arah toko, “Itu malingnya! Itu!”
Mereka menunjuk dia yang tadi beteriak minta
tolong. Gila, ini jebakkan. Tahu akan ini, dia berusaha
menjelaskan, namun para tukang parkir yang seper-
tinya berkomplot itu langsung menghajarnya. Lehernya
dicekik hingga tak dapat bersuara.
Bos muncul dengan mobil dan si perempuan. Dia
kaget mengetahui siapa yang sedang dihajar.
“Sudah kubiang ‘kan, dia itu dungu dan hanya men-
imbulkan kerugian,” kata si sopir.
Hampir saja perempuan yang di belakang itu mem-
Eko Triono __87
buka mulut, tapi rekan tukang parkir segera menarik
dan membiusnya di balik mobil tanpa ketahuan, lalu
menyembunyikannya.
“Coba geledah sakunya!” perintah tukang parkir,
seolah mewakili isi hati bos. “Dia telah berani meram-
pok jam emas paling berharga di kota ini. Dasar kutu
kupret!”
Seperti tersihir, orang-orang mengikuti apa yang
ia katakan. Beberapa pelacur yang melihat dari jen-
dela lantai dua dapat menyaksikan; lelaki malang
itu ditelanjangi—tinggal celana dalam. Pakaiannya
dikibas-kibaskan. Dan, tak ada sesuatu pun yang jatuh
menggerincing.
Takut ketiwasan, tukang parkir mencoba memas-
tikan sendiri. Dia mendekat.
“Di mana jam emas itu?!” ia atap wajah lelaki bodoh
yang sial, tak sampai sedetik lamanya.
“Aku tahu”—ia tempelkan telinga di sana—”tuh
‘kan benar apa dugaanku, aku dengar langkah waktu!”
sepertinya ada jawaban dari tatapan mata barusan. “Di
sini, di dadanya. Dia telah menelannya. Dasar brengsek.
Pisau! Man pisau?”
Rekannya memberi. Yang lain, atas dasar isyaratnya,
membungkam si tersangka yang tak berdaya.
Tanpa basa-basi, ia membedahnya dengan beranta-
kan, seperti ibu rumah tangga anyar yang baru belajar
membedah perut lele; dari ujung tulang dada, hingga
pusar.
Pada sesi pertema ia mengangkat tingi-tinggi usus-
usus yang menimbulkan bau jeroan manusia. Ia kemu-
dian meletakkannya begitu saja. Berikutnya, lambung.
Ia iris sambungannya, membedel, dan tak nemu apa-apa
88__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
juga. Kian panik, ia rogoh semuanya.
Tak kena juga jam emas itu. Uh! Wajah di sekeliling
mulai kesal, terutama bos.
“Ini dia....” tukang parkir itu nyengir senang sambil
terbaring, menarik tangan dengan hati-hati, merasa
menemukan kecurigaannya di bawah rongga dada kiri.
“Nah!” Ternyata salah.
“Jantung, bodoh! Itu jantung”—‘kan bos marah-ma-
rah jadinya—”mana jam emas itu? Mana? Ya, Tuhan...
kau bahkan telah membunuhnya,” dengar itu: bos bicara
dengan suara yang membenci diri sendiri, ketakutan
bukan main. Orang-orang pun berusaha membantunya
menyebut-nyebut nama Tuhan yang Maha Agung.
“Tapi sungguh, tadi suaranya seperti langkah
jarum jam, seperti detak waktu, bos,” tukang parkir
itu membela diri—dengan nada pura-pura sedih yang
mendalam—sembari menatap sebuah jantung yang
belepot merah dalam genggaman tangan kanannya
yang sunyi.[*]
Catatan: cerpen ini terinspirasi dari puisi Dwi S. Wibowo, Maling
Arloji.
Eko Triono __89
90__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Pulang
KITA HARUS PULANG. Sebentar lagi jam lima. Kemasi
barang-barangmu. Kita akan ikut kereta penghabisan.
Kita mesti segera pulang. Nanti, akan kutunjukan
padamu: mana itu ayah, mana itu ibu, dan mana itu adik.
Kau akan rasakan betapa menyenangkannya mereka.
Kita akan bermain di halaman; menyalakan kembang
api; membuat kincir daun di tepi sungai; bersepeda
di pematang; saling jaga dalam petak umpet—dan,
tertawa seperti burung-burung pagi yang berlompatan
di pohon jambu monyet. Kau tidak akan sedih di sana.
Ada sarapan yang menyenangkan. Obrolan yang riuh.
Ada kesibukan sederhana yang membuat lupa pada
kesedihan. “Tapi kenapa kita harus pulang?” Ya, karena
memang semestinya kita punya tempat pergi dan punya
tempat kembali. “Tapi kenapa harus pulang?” Karena
kita tak tahu lagi ke mana harus kembali. Sudahlah, kau
tidak lihat itu jam makin cepat? “Aku tak mau pulang.”
Eko Triono __91
Tapi kita harus pulang. “Tapi aku tak mau!” Harus mau!
“Kau saja sendiri.” Apa? Apa katamu? Sendiri? Kau dan
aku berada dalam satu nama, satu tubuh, satu ruh, dan
kau bilang aku harus pulang sendiri?[*]
92__ Kakek dan Cerita-cerita Lainnya
Riwayat Penerbitan
Ikan Kaleng disiarkan pertama kali di Kompas, 2011
Seekor Hiu di Atap Rumah disiarkan pertama kali di
Jurnal Nasional, 2013
Tahun-tahun Penjara disiarkan pertama kali dalam
kumpulan cerpen pilihan Taman Budaya Jawa
Tengah, Tahun-tahun Penjara, 2012
Kenapa Harus Saya pertama kali disiarkan di Kedaulatan
Rakyat dengan judul Doa Tukang Kebun, 2012
Bukan Aku yang Membunuhnya disiarkan pertama kali
di Majalah Sastra Horison, 2011
Eko Triono __93
Anda mungkin juga menyukai
- Malam Ketika Dia Menembak Dirinya (Kumpulan Cerpen)Dari EverandMalam Ketika Dia Menembak Dirinya (Kumpulan Cerpen)Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (1)
- Trilogi Pelelangan: Sebuah “Jane Eyre” Zaman Modern (Bahasa Indonesia)Dari EverandTrilogi Pelelangan: Sebuah “Jane Eyre” Zaman Modern (Bahasa Indonesia)Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (7)
- Pendekar Harum: Maling Romantis: Serial Pendekar HarumDari EverandPendekar Harum: Maling Romantis: Serial Pendekar HarumPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (10)
- Ringkasan Novel Laskar PelangiDokumen7 halamanRingkasan Novel Laskar PelangiOktaviana Ayu90% (10)
- Si Pembuat Jam Tangan: Sebuah Novel (Bahasa Malayu)Dari EverandSi Pembuat Jam Tangan: Sebuah Novel (Bahasa Malayu)Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (2)
- Rahasia Salinem-Isi Novel-Fix-FinalDokumen389 halamanRahasia Salinem-Isi Novel-Fix-Finalisirambutan0% (1)
- Penjelmaan (Buku #1 dalam Harian Vampir)Dari EverandPenjelmaan (Buku #1 dalam Harian Vampir)Penilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (9)
- Sinopsis Edensor Per BabDokumen4 halamanSinopsis Edensor Per BabFendy Fendy100% (2)
- Kumpulan Cerpen KompasDokumen6 halamanKumpulan Cerpen KompasAyu Puspa NandaBelum ada peringkat
- Maryamah KarpovDokumen378 halamanMaryamah Karpovgamal ahmadBelum ada peringkat
- Siti NurbayaDokumen31 halamanSiti NurbayasagalaayawaeBelum ada peringkat
- Soal Latihan Pas Xii 23Dokumen4 halamanSoal Latihan Pas Xii 23sofiaturrohmah102Belum ada peringkat
- Novel 1Dokumen30 halamanNovel 1Mezi GraseliaBelum ada peringkat
- Novel Maryamah Karpov PDFDokumen136 halamanNovel Maryamah Karpov PDFBayu Aji DermawanBelum ada peringkat
- Andrea Hirata Maryamah KarpovDokumen141 halamanAndrea Hirata Maryamah KarpovIndriyani AnthonieBelum ada peringkat
- Dewi 'Dee' Lestari - Perahu KertasDokumen45 halamanDewi 'Dee' Lestari - Perahu KertasWinni WinniyartiBelum ada peringkat
- Topeng Hitam KelamDokumen70 halamanTopeng Hitam KelamErvan MappangaraBelum ada peringkat
- Novel Tetralogi Andrea Hirata Sang PemimpiDokumen118 halamanNovel Tetralogi Andrea Hirata Sang PemimpiDenia AzahraBelum ada peringkat
- Si Babi HutanDokumen3 halamanSi Babi HutanNana ChannelBelum ada peringkat
- KemarauDokumen5 halamanKemarauGenevraBelum ada peringkat
- Kasih Yang Tak SampaiDokumen13 halamanKasih Yang Tak SampaihernandorahmanBelum ada peringkat
- Kumpulan PuisiDokumen9 halamanKumpulan PuisiBusro BainaBelum ada peringkat
- Cerpen, Angin Menabuh DaunDokumen2 halamanCerpen, Angin Menabuh DaunLanang WongBelum ada peringkat
- Soal N Jawaban Semester 1 Kls X - Tanpa JawabanDokumen16 halamanSoal N Jawaban Semester 1 Kls X - Tanpa JawabanVira OmotBelum ada peringkat
- Soal N Jawaban Semester 1 Kls XDokumen16 halamanSoal N Jawaban Semester 1 Kls XVira OmotBelum ada peringkat
- 40 Contoh Puisi Pendek Berbagai Tema Yang Penuh MaknaDokumen39 halaman40 Contoh Puisi Pendek Berbagai Tema Yang Penuh MaknaResdy BenyaminBelum ada peringkat
- Amsterdam, Juni 1999 ... : Perahu KertasDokumen4 halamanAmsterdam, Juni 1999 ... : Perahu KertasErnes ToraBelum ada peringkat
- Makalah Analisis Novel Keluarga CemaraDokumen8 halamanMakalah Analisis Novel Keluarga CemaraHaris Satrio UtomoBelum ada peringkat
- Analisis Unsur Instrinsik Dan Ekstrinsik Cerpen KuntowijoyoDokumen8 halamanAnalisis Unsur Instrinsik Dan Ekstrinsik Cerpen KuntowijoyoSofyan HadiNataBelum ada peringkat
- Alur Dan Latar Kelompok 5Dokumen6 halamanAlur Dan Latar Kelompok 5Gentry Awali RahmaBelum ada peringkat
- Cerpen SulaimanDokumen24 halamanCerpen SulaimanAfan Anas Al HakimBelum ada peringkat
- Prisilia Desita AryantiDokumen19 halamanPrisilia Desita AryantiDesita Prisilia Desita AryantiBelum ada peringkat
- Naskah Drama - Abrar RabbaniDokumen6 halamanNaskah Drama - Abrar Rabbaniabor nipponBelum ada peringkat
- Anak Tani - Laura Ingalls WilderDokumen125 halamanAnak Tani - Laura Ingalls WilderJuniti 15Belum ada peringkat
- Qhprte 1592808560Dokumen381 halamanQhprte 1592808560Ni KiBelum ada peringkat
- Analisis Novel Anak Pintar - Muhammad Tarqi69Dokumen6 halamanAnalisis Novel Anak Pintar - Muhammad Tarqi69Bions GERBelum ada peringkat
- Seputih Jilbab Fransiska (Isi)Dokumen218 halamanSeputih Jilbab Fransiska (Isi)SumarnoBelum ada peringkat
- Cerpen KemarauDokumen4 halamanCerpen KemarauanjelirahmiBelum ada peringkat
- PerahuDokumen32 halamanPerahuKrisna NdogceplokBelum ada peringkat
- Pendekar GilaDokumen177 halamanPendekar GilaHerman EfBelum ada peringkat
- Jalan Menulis PentigrafDokumen19 halamanJalan Menulis PentigrafRodearny purbaBelum ada peringkat
- Kritik Kebijakan Kurikulum - Sandi Budi Iriawan - RevisiDokumen58 halamanKritik Kebijakan Kurikulum - Sandi Budi Iriawan - Revisial-majnunBelum ada peringkat
- FactSheet - Ekosistem Teknologi Kemendikbudristek - Harteknas 2022Dokumen1 halamanFactSheet - Ekosistem Teknologi Kemendikbudristek - Harteknas 2022al-majnunBelum ada peringkat
- Soal Games Ranking 1Dokumen3 halamanSoal Games Ranking 1al-majnunBelum ada peringkat
- Supervisi Guru Kelas Dan MapelDokumen2 halamanSupervisi Guru Kelas Dan Mapelal-majnunBelum ada peringkat
- Team Building Games v.2Dokumen14 halamanTeam Building Games v.2al-majnunBelum ada peringkat
- Form Penilaian Team Building Games. - v.2Dokumen4 halamanForm Penilaian Team Building Games. - v.2al-majnunBelum ada peringkat
- Belajar & BerprestasiDokumen7 halamanBelajar & Berprestasial-majnunBelum ada peringkat

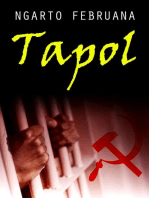


![Cinta 3 Sisi [Not English]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/193352986/149x198/33613985e3/1676587903?v=1)