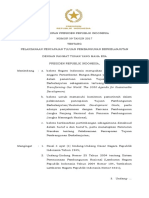Isme Isme
Diunggah oleh
Into HyasintusJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Isme Isme
Diunggah oleh
Into HyasintusHak Cipta:
Format Tersedia
FILSAFAT DAN PERWUJUDAN DIRI (Belajar Filsafat dan Berfilsafat) Oleh Konrad Kebung
Filsafat harus diajarkan sekian rupa sehingga para mahasiswa memperoleh suatu pemahaman yang benar dan kokoh tentang manusia, alam dan Tuhan. Mereka juga dapat mempelajari filsafat jamannya terutama filsafat yang sangat berpengaruh dari dan dalam daerahnya sendiri atau dalam hubungan dengan perkembangan ilmu-ilmu terbaru. Sejarah filsafat harus diajarkan sekian rupa sehingga para mahasiswa, dengan memahami prinsipprinsip dasar pelbagai sistem, menentukan mana yang benar dan harus diterima, dan mana yang salah dan karena itu harus ditolak. Metode mengajar hendaknya mengutamakan inspirasi dan menanam sikap mencinta untuk mencari, menghargai dan membela kebenaran serta pengakuan yang jujur atas batas-batas pemahaman manusia. Kaitan antara filsafat dan masalah-masalah yang benar tentang hidup harus diutarakan dengan saksama, demikian pula hubungan filsafat dengan masalah-masalah yang sungguh mempengaruhi pikiran para mahasiswa. Para mahasiswa juga dibantu untuk melihat kaitan-kaitan antara argumen filosofis dengan misteri-misteri keselamatan pokok-pokok yang menjadi inti bahasan dalam teologi di bawah bimbingan cahaya iman.[1]
Pendahuluan Sejak berdirinya Seminari Tinggi Ledalero pada tahun 1935 (berawal di Mataloko dan berpindah ke Ledalero pada tahun 1937), mata kuliah filsafat sudah diajarkan di sini disanding dengan teologi sebagai bidang studi utama untuk pendidikan calon imam, biarawan dan misionaris. Secara tradisional filsafat dilihat sebagai ilmu yang lebih berbicara tantang manusia dan tata alami sedangkan teologi berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan atau Yang ilahi melalui iman dan wahyu. Di universitas-universitas besar tempo dulu di mana ada jurusan teologi di sana juga terdapat jurusan atau studi-studi filsafat. Teologi, sebagai refleksi manusia atas iman dan wahyu ilahi dalam terang akal budi manusia harus didukung oleh studi-studi filsafat yang berurusan dengan manusia dan tata alami. Diterangi oleh filsafat abad pertengahan dan Skolastisisme yang bercorak teosentris teologi, sebagai ilmu yang membuat refleksi tentang Tuhan dan pelbagai atributnya, dilihat sebagai ilmu yang lebih luhur ketimbang studi-studi tentang alam dan manusia. Dalam terang ini filsafat selalu dilihat sebagai pelayan teologi (ancilla theologiae). Pemahaman seperti ini bahkan masih membekas hingga zaman kini dan ini jelas terlihat dalam sistem, jenjang dan kurikulum pendidikan calon imam, yaitu bahwa teologi harus dipelajari setelah studi filsafat. Karena itu di seminari-seminari tinggi selalu ada pembagian dalam unit filosoficum (untuk yang tengah belajar filsafat) dan teologicum (bagi yang tengah mempelajari teologi dan persiapan akhir untuk kaul-kaul dan tahbisan-tahbisan suci). Dalam pemahaman ini, seorang harus lebih dulu menyelesaikan studi filsafat sebelum ia melangkah ke studi teologi. Namun sejalan dengan proses berpikir manusia pada umumnya dan bahwa ilmu-ilmu semakin memiliki kekhasan dalam dunia berpikir, pemahaman filsafat sebagai pelayan teologi pun bergeser. Studi filsafat dilihat sebagai bagian paling penting untuk memahami gagasan-gagasan dan ide dalam teologi dan keduanya kini memiliki hubungan kemitraan dan
tidak lagi hubungan atas-bawah, lebih luhur-lebih rendah, dan yang serupa. Justru dalam berteologi orang dapat berfilsafat dan dalam berfilsafat orang juga dapat berteologi. Ensiklik mendiang Sri Paus Yohanes Paulus II, Fides et Ratio (14 September 1998) mengemukakan suatu pemahaman yang seimbang antara filsafat dan teologi. Sri Paus menegaskan bahwa filsafat tidak melulu dilihat sebagai persiapan bagi teologi dan karena itu bukan lagi ancilla theologiae. Keduanya justru dilihat sebagai mitra-mitra dalam tugas yang sama untuk menemukan dan mencapai kebenaran yang universal dan transenden. Di sini Sri Paus menegaskan adanya satu matra religius dalam filsafat dan satu matra filosofis dalam teologi, mengingat objek keduanya adalah kebenaran yang terdalam dan transenden. Dalam artian ini hubungan antar filsafat dan teologi dapat dijelaskan sebagai satu terkandung di dalam yang lain. Melalui pandangan yang lebih seimbang seperti ini kita dapat berbicara dan memahami integrasi filsafat dan teologi. Di Ledalero sejak tahun 70-an sudah banyak dibicarakan dan dipraktikkan integrasi kuliah filsafat dan teologi. Sejak pada level filsafat para mahasiswa juga sudah mempelajari banyak perkuliahan teologi. Untuk itu saya ingin mengetengahkan garis besar pengajaran filsafat yang pernah diberikan di Ledalero dalam perjalanan sejarah Seminari. Di sini saya tidak berbicara tentang pelbagai disiplin filsafat yang pernah disajikan di ruang kuliah. Yang lebih saya soroti dalam kaitan dengan proses berpikir kita adalah menyangkut isi (content), orientasi dan metode perkuliahan, serta hasil atau tanggapan dari mahasiswa. Melalui uraian singkat ini kita dapat memahami perkembangan proses berpikir manusia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Lewat mengikuti perkembangan proses berpikir ini kita juga dapat memahami bagaimana orang berfilsafat dari masa ke masa sesuai dengan konteks hidup mereka. 1. Belajar Filsafat dan Berfilsafat Kita sering mendengar para mahasiswa berkisah tentang bagaimana mereka belajar filsafat. Sebagai suatu ilmu yang belum terlalu populer di mata dan pikiran kebanyakan orang di wilayah kita, masih terdapat terlalu banyak prasangka terhadap filsafat. Filsafat dianggap sebagai ilmu yang sukar, suatu studi tentang objek-objek spekulatif yang bersifat abstrak dan penuh rahasia, atau kemampuan memanipulasi pikiran sederhana atau pengungkapan ide-ide sederhana dalam bahasa dan terminologi yang hebat, bombastik dan sukar; ilmu yang tidak memiliki nilai dalam kehidupan praktis, hanya menekankan konsep dan teori, pemutarbalikkan sistematis dari semua pandangan dan pikiran sederhana dan biasa, dan pengganggu iman kristen yang sangat dogmatis.[2] Prasangka-prasangka ini merupakan tantangan besar dalam dunia filsafat, dan karena itu filsafat kerap dituding sebagai pengganggu iman dan ajaran Kristen, bahkan dalam kalangan religius ada anggapan bahwa studi filsafat kerap dicurigai sebagai ajang kejatuhan atau kegagalan para imam atau biarawan. Justru melalui pandangan-pandangan yang tidak seimbang berdasarkan prasangka di atas dan karena filsafat itu selalu dilihat (terlalu sempit) sebagai ilmu, yang memiliki objek yang pasti, maka filsafat akhirnya dilihat sebagai suatu ilmu yang berat dan sukar. Immanuel Kant ( 1724-1804 ) adalah pemikir Jerman yang secara eksplisit memerotes kenyataan ini. Menurut Kant, kita tidak belajar filsafat melainkan berfilsafat. Belajar filsafat berarti melihat filsafat melulu sebagai suatu ilmu tertutup sebagaimana kita mempelajari sejarah atau suatu objek material tertentu. Kita seharusnya berfilsafat. Itu berarti kita selalu harus mampu berpikir sendiri, berdaya kreasi dan berusaha untuk selalu menemukan sesuatu yang baru. Filsafat merupakan suatu proses berpikir yang hidup dan bukannya suatu ilmu mati. Filsafat adalah suatu proses atau usaha pencaharian yang terus menerus; suatu cara berpikir yang terbuka bukan seperti ilmu pada umumnya yang selalu menuntut jawaban-jawaban tertentu sesuai dengan objeknya. Filsafat juga merupakan sebuah pertanyaan dan bukannya tanda seru
(!), pernyataan (statement) atau proposisi. Justru dalam keterbukaan seperti ini filsafat berbeda dari ideologi atau dogma yang pada umumnya bersifat tertutup.[3] 1.1. Filsafat dan Hidup Para pemula dalam bidang filsafat biasanya sangat cemas ketika mereka mulai memasuki bidang studi ini. Keraguan dan kecemasan ini biasanya pelan-pelan pudar ketika orang sudah mulai menekuni bidang ini. Dan terasa lebih menarik lagi ketika orang sadar bahwa filsafat adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka. Anda tidak perlu mencari jauh-jauh apa kiranya yang menjadi inti filsafat. Ternyata tanpa Anda sadar, Anda telah berfilsafat. Persoalan menyangkut hidup adalah persoalan universal yang dihadapi oleh setiap manusia di mana saja. Sejak masa kanak-kanak orang sudah mulai melontarkan banyak pertanyaan dan menemukan jawaban-jawabannya tersendiri mengenai hidup ini. Banyak pertanyaan sering keluar dari persoalan-persoalan biasa dalam hidup, tetapi kadangkala pertanyaan itu melenceng jauh di luar pemahaman dan daya jangkau akal manusia itu sendiri. Setiap orang mampu melontarkan pertanyaan tentang hidup dan pengalamannya, dan senantiasa berusaha untuk menemukan jawaban atas pelbagai pertanyaan dan persoalan hidupnya. Dan karena setiap orang dapat bertanya dan memberikan jawaban, maka juga setiap orang dapat berfilsafat. Kalau setiap orang dapat melontarkan pertanyaan dan dapat berfilsafat serta dapat menemukan jawabannya tersendiri, untuk apa kita masih membutuhkan para pakar dalam dunia filsafat, yang memiliki kesibukan berpikir dan membuat rencana bagaimana mereka harus menata hidup ini. Setiap ahli filsafat tentu juga tidak bisa memberikan suatu jawaban absolut yang berlaku untuk semua orang dalam setiap lingkungan dan fase sejarah.[4] Namun kenyataan bahwa seorang ahli filsafat masih sangat berguna dalam membantu memecahkan banyak masalah dalam kehidupan manusia. Ia tampil sebagai seorang dokter yang dapat mendiagnose penyakit dan menunjukkan permasalahan serta memberikan terapi yang tepat untuk penyakit itu. Filsafat membahas pelbagai macam permasalahan manusia sehari-hari. Pada beberapa dasawarsa terakhir, para filsuf di dunia barat lebih memperhatikan sejarah filsafat dengan pelbagai peristilahan (seperti logika, semantika, analisis bahasa, dll). Filsafat eksistensialisme justru mulai membahas dan melihat masalah-masalah manusiawi yang dihadapi setiap makhluk rasional seperti perasaan cemas dan takut, ideal atau harapan, keterbatasan manusia, pilihan dan kebebasan, penderitaan dan kematian, dan lain sebagainya. Fenemenologi[5]menekankan keterbukaan kepada realitas atau pengungkapan diri realitas kepada kesadaran atau subjek. Dengan kata lain, subjek membiarkan diri disentuh oleh realitas. Karena itu ia (subjek) bersifat menerima (reseptif) dan bukannya secara aktif memanipulasi realitas. Filsafat sejati hendaknya tidak asing dari hidup ini. Ia justru berdasar pada hidup dan memperkaya hidup ini. Filsafat juga dilihat sebagai puncak perkembangan hidup dan kebudayaan seorang manusia. Macam filsafat manakah yang harus seseorang miliki tergantung pada situasi dan karakter serta pendidikan seseorang. Menurut kata-kata Fichte, filsafat macam manakah yang diemban seseorang tergantung pada manusia macam manakah orang itu. Seorang filsuf hendaknya tetap terbuka terhadap realitas. Ia seharusnya profesional dalam bidangnya dan dalam hidup ini. Ia harus pandai menghadapi masyarakat dan mampu melihat setiap situasi secara positip dan matang. Dalam perjalanan sejarah filsafat kita melihat bahwa para pemikir betul berfilsafat mengenai lingkungan mereka. Para filsuf pra-Sokrates, yang pada umumnya adalah ahli-ahli kosmologi, (yang sekarang seharusnya dikelompokkan sebagai saintis) hanya berkecimpung
dalam dunia mereka ini, karena hal ini dilihat sebagai pengetahuan dan pengalaman umum yang banyak didiskusikan orang. Mereka mempersoalkan asas atau prinsip (arche) yang menjadi dasar terjadinya segala sesuatu. Thales menyebut air sebagai asas dasar, Anaximander menyebut sesuatu yang tak terbatas (to apeiron), Anaximenes menyebut udara dan Heraklitus menyebut api sebagai asas, dan lain sebagainya. Sokrates, Plato dan Aristoteles berfilsafat tentang manusia: keyakinan dan kebudayaan serta pandangan hidup, apa yang manusia tahu dan pikirkan dan apa yang mereka alami dan hidupi. Dialog Platonik atau tulisan-tulisan Aristoteles yang dihimpun dalam The Basic Works of Aristotle sungguh membenarkan ini.[6] Seluruh ide dan karya berpikir mereka mencerminkan hidup dan pengalaman mereka sendiri dan pengalaman manusia pada umumnya. Para filsuf sesudahnya juga berfilsafat tentang realitas yang mereka alami. Singkatnya seluruh filsafat berpikir paling kurang mencerminkan realitas hidup dan lingkungan hidup manusia sendiri. Perlu kita sadari bahwa para filsuf adalah para pemikir. Mereka meluangkan banyak waktu untuk berpikir dan berefleksi. Dan berpikir dalam artian yang sebenarnya adalah berkonfrontasi dengan realitas konkret kehidupan kita. Dan karena itu para filsuf dari setiap era peradaban dan era berpikir dalam artian ini sudah berfilsafat secara kontekstual. Konteks hidup mereka telah menggerakkan mereka untuk berfilsafat. Ada banyak pemikir berfilsafat dengan mendasarkan diri pada konteks sosial ekonomis (seperti Karl Marx dan Adam Smith), ada yang berfilsafat dalam konteks politis (Habermas, Chomsky), konteks pengetahuan dan ilmu pengetahuan (Bachelaard, Foucault, Kuhn, Feyerabend), konteks psikologis (Nietzsche, Buber, Freud), konteks seni, moral dan etika, dan lain sebagainya.
1.2. Perkuliahan Filsafat di Seminari Tinggi Ledalero (STFK) Sejak dimulainya Seminari ini tahun 1937 di Ledalero, filsafat telah dikuliahkan, disanding dengan teologi sebagai mata kuliah dasar pendidikan calon imam, biarawan dan misionaris. Pada beberapa tahun awal perkuliahan diberikan dalam bahasa Belanda dan kemudian cukup lama diberikan dalam bahasa Latin, bahasa resmi Gereja, peninggalan abad pertengahan. Dengan jumlah tenaga dosen dan keahlian dalam fak yang sangat terbatas, dan kemampuan bahasa Latin yang minim kita bisa membayangkan betapa para mahasiswa kita memahami filsafat. Pada masa Konsili Vatikan II diserukan macam-macam pembaruan dalam Gereja, antara lain menyangkut kebudayaan, tatacara liturgis, pendidikan, bahasa, dan yang serupa. Maka perkuliahan juga mulai diberikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa pribumi. Isi dan metodologi perkuliahan pada masa itu tentu disesuaikan dengan cara berpikir zaman itu - lebih banyak terfokus pada gagasan-gagasan dan ide-ide besar masa lalu, dan bagaimana ide atau gagasan ini dipelajari dan dimengerti oleh para mahasiswa. Penekanan dalam perkuliahan filsafat ialah usaha untuk menemukan ide-ide baru dan bagaimana ide itu bisa menguasai dunia pemikiran manusia dan diteruskan kepada generasi-generasi berikut. Kebenaran filsafat diyakini sebagai yang bersifat tetap dan lestari. Mahasiswa diyakinkan untuk belajar atau menghafal, dan selebihnya merupakan tugas pribadi mahasiswa untuk menggelutinya lebih dalam dan mengambil manfaat dari bahasan-bahasan itu. Sampai 1969 bidang akademik langsung ditangani oleh Seminari Tinggi Ledalero di bawah Rektor dan Dewan Rumah, dengan menugaskan seseorang yang mampu untuk memegang jabatan sebagai direktur studi. Sejak Januari 1969 Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Katolik (STFTK) secara resmi berdiri sebagai salah satu bagian dari Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero. Sejak saat itu pimpian STFTK dikenal dengan nama Ketua Sekolah.
Sejak tahun 1980-an kata teologi didrop dan untuk seluruh program S1 yang berada di bawah jurusan Filsafat Agama Katolik ini dikenal dengan nama STFK. Pada tahun 1970-an ketika kami memasuki STFTK seluruh perkuliahan sudah diberikan dalam bahasa Indonesia (sudah dimulai pada tahun 60-an), kecuali beberapa dosen tamu yang selalu memberikan kuliah dalam bahasa Inggris. Perkuliahan filsafat berjalan seperti biasa dengan jumlah dosen yang jauh di bawah memadai. Para mahasiswa memperoleh pelajaran filsafat seadanya sesuai dengan kemampuan dan keahlian dosen yang ada. Warna-warna perkuliahan yang diberikan lebih menekankan hafalan. Para mahasiswa diharuskan untuk mempelajari pelbagai gagasan atau ide yang dipaparkan dan bisa memenuhi tuntutan sekolah sambil kurang sekali menekankan daya kreasi dan keaktipan berpikir para mahasiswa sendiri. Kalau mahasiswa aktif dan kreatif ia akan memperoleh banyak keuntungan. Kalau tidak demikian maka pengetahuan filsafat orang itu hanya sebatas yang ia pelajari dan ingat, dan karena itu sangat kerdil dan mandul. Sejak tahun 1990-an hingga sekarang jumlah dosen filsafat bertambah dan semakin banyak disiplin filsafat ditawarkan kepada para mahasiswa. Kuliah-kuliah pilihan dan seminar semakin marak berbarengan dengan sekian banyak disiplin filsafat yang lebih menyentuh isu-isu kemanusiaan pada umumnya. Selain dari itu filsafat mendapat dukungan sangat kuat dan semakin menarik dengan adanya sekian banyak disiplin ilmu sosial dan ilmuilmu humaniora yang ditawarkan dalam perkuliahan. Dengan itu kuliah-kuliah filsafat menjadi semakin menarik dan menyentuh kebutuhan dan minat banyak mahasiswa. Suatu warna khusus yang mulai tampak pada dekade ini ialah bahwa daya kreasi para mahasiswa mulai mendapat lebih banyak perhatian. Para mahasiswa harus berpikir dan berefleksi tidak hanya mengenai teori-teori besar filsafat yang ia peroleh, tetapi juga mulai memperhatikan aspek pragmatis dari semua perkuliahan ini, terutama bagaimana teori-teori itu dapat diterjemahkan dalam tingkah laku dan praktik kehidupan. Mahasiswa lebih dipacu untuk berpikir dan berdaya kreasi. Pikiran-pikiran kritis mulai tampak dan para mahaasiswa pelanpelan diarahkan kepada lingkungan dan pengalaman konkret hidup mereka. Dalam beberapa tahun terakhir ini gejala ini sudah sangat kuat tampak dalam diri para mahasiswa. Banyak yang mulai lebih memperhatikan situasi konkret kehidupan mereka. Pelbagai isu dan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat menjadi perhatian serius mereka. Dan banyak dari antara mereka mulai menyuarakan pandangan-pandangan kritis mereka terhadap kemelut yang ada dalam hidup mereka sendiri secara pribadi dan secara sosial dalam hidup bermasyarakat; entah itu kemelut dalam kaitan dengan keadilan dan perdamaian, sosial-politis, hak dan kewajiban, moral-etis, dan yang serupa. Banyak mahasiswa dan para dosen melibatkan diri dalam pelbagai aktivitas yang menyuarakan suarasuara kritis kenabian untuk membela hak-hak orang yang ditekan atau coba menyuarakan jeritan dan tangisan tak bersuara dari masyarakat kecil dan terpinggirkan terhadap kesewenangan para penguasa, diktator dan para pemimpin otoriter lainnya. Paper-paper, skripsi-skripsi, diskusi dan seminar mereka lebih banyak diwarnai oleh gambaran situasi konkret, sekaligus mencerminkan corak berpikir seperti ini. Jelas bahwa mereka tengah berfilsafat dalam situasi konkret hidup mereka. Dengan ini para mahasiswa pelan-pelan meninggalkan filsafat sebagai bahan kuliah yang mereka pelajari kepada karya berfilsafat itu sendiri. Di sini sudah jelas terlihat bahwa, lewat dukungan dari sekian banyak ilmu lain, filsafat menjadi semakin kontekstual dan menyentuh serta dapat menjawabi kebutuhan banyak manusia. Sifat kontekstual menjadi lebih nyata karena seluruh isi pemikiran dan refleksi serta energi kita diarahkan kepada realitas konkret kehidupan kita.
2. Filsafat dan Perwujudan Diri[7] Tujuan yang paling dekat dari segala kegiataan pembelajaran ialah untuk memperoleh pengetahuan tentang apa yang dipelajari. Namun tujuan ini masih bersifat sementara dan dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain sesudahnya (end as means). Dan tujuan yang ultim dari semua aktivitas pembelajaran dan perolehan pengetahuan adalah menjadi matang dan dewasa dalam pelbagai aspek atau perwujudan diri secara penuh (end in itself). Demikian pula filsafat sebagai ilmu dipelajari dengan tujuan untuk mencapai kebenaran, namun kebenaran ini harus mengarahkan kita kepada perwujudan diri kita sebagai manusia (pemanusiaan diri kita). Filsafat, menurut arti kata yang sebenarnya, adalah cinta akan kebijaksanaan, dan karena itu filsafat seharusnya lebih dilihat sebagai pandangan hidup: bagaimana seorang manusia memandang dunianya, berpikir dan memahami dunia dan lingkungannya, dan bagaimana ia menata hidupnya dalam dan bersama dengan dunianya. Filsafat juga dilihat sebagai ilmu yang membutuhkan refleksi dan pemikiran sistematis-metodis dengan secara aktif menggunakan intelek dan rasio kita. Namun filsafat sebagai pandangan hidup dan sebagai ilmu tidak terpisah satu sama lain, melainkan berkaitan sangat erat, malahan saling memuat dan mencakupi melalui karya rasional yang abstrak-spekulatif namun berpijak pada alam kosmis yang konkret dan riil ini. Lewat berpikir dan berefleksi, kita sebenarnya mengonfrontasikan diri dengan lingkungan-dunia dan bagaimana kita memandang dan memahami diri kita. Kaitan erat antara filsafat sebagai pandangan hidup dan sebagai ilmu dapat kita lihat dalam biografi setiap filsuf dalam setiap era berpikir manusia. Saya hanya menyebut beberapa nama yang secara eksplisit berbicara tentang pokok ini, terutama kaitan erat antara berpikir dengan kehidupan konkret hidup dan estetika, kehidupan praktiskonkret. Di sini kita bisa melihat bagaimana filsafat langsung berhubungan dengan pembentukan sikap, kepribadian dan transendensi serta transformasi diri manusia. Sokrates tidak pernah menulis buku tetapi ia menghidupkan kebijaksanaan dalam dirinya sendiri. Di sana filsafat sungguh dilihat sebagai praktik hidup atau seni hidup (estetika). Dia berjalan keliling sambil berfilsafat dan dia akhirnya juga mengorbankan hidupnya sendiri demi filsafat dan kebenaran (bdk. Apology). Sokrates justru menyebut filsuf sebagai guru erotika yang menyediakan paradigma hidup filosofis. Kehadirannya yang hidup, studinya yang tidak pernah kenal lelah, keindahan hidup yang menarik, dan stylenya yang tidak biasa (bukan bersifat umum) menarik kaum muda zamannya. Melalui Plato, yang menghimpun dan menulis kembali semua gagasan Sokrates, kita tahu sangat banyak tentang Sokrates.[8] Dia sungguh seorang pemikir yang tidak hanya sekadar mengungkapkan ide-ide abstrak, melainkan yang juga berbicara tentang filsafat ini dalam hidupnya sendiri, dan yang sungguh memperjelas tugas filsafat sebagai bantuan dalam pembentukan diri (self-formation).[9] Dalam dialog dengan patner bicaranya, Sokrates ingin agar, lewat bertanya dan mempersoalkan, patner bicaranya mampu mengekspresikan dirinya sendiri. Dia membentuk dalam diri patner bicaranya suatu sikap kreatif dan percaya serta sadar diri, dan dengan demikian ia dapat menemukan jatidirinya sendiri. Ia mengatakan yang benar (truth-telling) dalam suatu pertemuan yang lebih personal dan dialogal.[10] Selain dari ini dalam dialog-dialog seperti Crito, Gorgias, dan Politeia (Republic) peran seorang filsuf dilihat sebagai analog dengan peran seorang dokter. Dokter menangani kesehatan tubuh, filsuf menangani kesehatan mental-jiwa. Di sana ia banyak berbicara tentang suatu model quasi-medis yang menangani kesehatan dan suatu model estetis tentang seni dan keindahan.[11] Aristoteles, sebagai seorang realis, berbicara tentang hampir semua dimensi hidup manusia mulai dari aspek biologis-material dan natural sampai pada aspek mental-psikologis dalam seluruh karyanya.[12] Dia membedakan pengetahuan teoretis-spekulatif (matematis)
dan pengetahuan praktis yang hanya dapat dipelajari melalui tindakan dan praktik - suatu praktik yang secara konkret terbentuk dalam diri. Kalau kita membaca buku Nocomachean Ethics, kita dapat menemukan pelbagai ajaran moral-psikologis dan pembentukan hidup pribadi dan komunal. Filsafat sungguh dilihat sebagai suatu praktik hidup dan formasi diri yang dewasa dan penuh.[13] Dalam karya ini dikemukakan kebajikan-kebajikan manusiawi yang hanya dapat dikembangkan lewat praktik hidup demi pendewasaan dan kebahagiaan hidup manusia. Beberapa pemikir lain yang secara eksplisit dan luas berbicara tentang filsafat sebagai praktik hidup dengan peran khusus dalam transformasi diri adalah John Dewey (1859-1952), Ludwig Wittgenstein (1889- 1951), dan Michel Foucault (1926-1984). Dari biografi mereka yang sekian luas dan kaya dua fenomena utama yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut: Pertama, kendati filsafat semakin merosot dalam otoritas dan prestise, ia selalu menarik perhatian dalam kebudayaan intelektual kita. Dengan itu para filsuf masih dapat berfungsi sebagai pahlawan yang riwayat hidupnya dapat dibaca, dinikmati dan didayagunakan. Kedua, sukses besar dari biografi mereka memperlihatkan titik lemah dari keterpisahan antara filsafat profesional yang dilembagakan dari pemikiran filosofis dengan hidup personal yang konkret. Bagi mereka, pemikiran filosofis berkaitan sangat erat dengan pengalaman pribadi dan hidup konkret. Dewey misalnya mengakui bahwa filsafatnya merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman personal. Ia lebih berasal dari pribadi-pribadi dan situasi-situasi daripada dari buku-buku. Wittgenstein mempersoalkan bagaimana menghadapi suatu hidup yang baik dan bahagia? Live well, ia katakan sebagai hukum filosofis tertinggi.[14]Filsafat memiliki tugas yang jauh lebih penting dan eksistensial, yaitu menolong kita kepada hidup yang lebih baik melalui usaha perbaikan diri - pengetahuan tentang diri, kritik diri dan penguasaan diri. Bagi para filsuf ini filsafat lebih daripada sekadar berpikir dan berteori. Ia merupakan praktik hidup di mana teori memperoleh maknanya yang riil dan teori bermakna hanya dalam hubungan dengan hidup di mana ia berfungsi dan menemukan hidup yang lebih baik secara konkret (pragmatisme). Pragmatisme Dewey menekankan fungsi ultim yang praktis dan lebih mengutamakan hidup dari filsafat. Sebagai suatu seni komprehensif dari tingkah hidup yang bijaksana, filsafat adalah suatu kritik tentang hidup agar dapat diperoleh suatu apresiasi intensif dan adil tentang makna yang ada dalam pengalaman.[15] Kita menemukan kiatan erat antara pemikiran filosofis tentang kondisi hidup seseorang dan usaha filsafat untuk meningkatkan kondisi-kondisi itu (hidup dan berpikir) dengan mengubah kondisi sendiri melalui refleksi kritis. Wittgenstein dalam Culture and Value (CV), melihat hubungan filsafat dengan persoalan-persoalan hidup (hlm 4). Anda harus merubah cara hidup anda (hlm 27). Dengan ini jelas bahwa nilai filsafat diperoleh dari konteks hidupnya dan usaha mengejar hidup yang lebih baik (hlm 22). Bagi Wittgenstein, filsafat sebenarnya ditulis hanya sebagai suatu komposisi puitis. Karena seperti karya artis pemikiran filsuf dapat berhasil menangkap dunia sebagai praktik transformasional, menyiapkan suatu visi di mana ia dapat melihat hidupnya sebagai suatu karya seni (CV, hlm. 4-5; 24). Bekerja dalam filsafat seperti karya arsitektur dalam banyak hal lebih merupakan suatu penataan diri. Sebagai mana hidup bahagia sebagai tujuan filsafat demikian pula yang indah adalah apa yang mendatangkan kebahagiaan. Seni yang memandang dunia dengan suatu mata bahagia memiliki keindahan sebagai tujuan akhirnya.[16] Michel Foucault menekankan hidup filosofis sebagai privilese utama filsafat. Pahampaham filsafatnya lebih mudah dimengerti lewat episode-episode dan praktik-praktik tertentu dalam hidupnya. Ia menggeneralisir bahwa kunci menuju sikap poetik yang personal dari seorang filsuf bukan ditemukan dalam ide-ide atau gagasan-gagasannya, seakan dia dapat
dideduksikan dari ide-ide ini, melainkan ditemukan dalam filsafatnya sebagai hidup, dalam kehidupan filosofisnya, dalam etosnya.[17] Filsafat menjadi suatu praktik hidup, di mana diri ini ditransfigurasi melalui eksperimen, disiplin dan siksaan (lingkungan yang penuh cobaan). Menurut Foucault, ontologi penting dari diri kita harus dilihat bukan sebagai sebuah teori atau doktrin, bukan juga suatu tubuh pengetahuan yang permanen dan akumulatif, melainkan sebagai suatu sikap, suatu etos, suatu hidup filosofis, di dalamnya kritik tentang siapa atau apakah kita sekaligus merupakan analisis historis tentang batas-batas yang dipaksakan (imposed) kepada kita dan suatu eksperimen dengan suatu kemungkinan untuk melampaui batas-batas ini (transendensi).[18] Dalam kaitan dengan estetika, Foucault melihat ideal hidup estetik berakar dalam di dalam kebudayaan Yunani klasik yang mempraktikkan estetika eksistensi, ungkapan kehendak untuk menghidupkan suatu hidup yang lebih indah, dan meninggalkan untuk orang lain kenangan-kenangan akan suatu eksistensi yang indah.[19] Bagi Foucault, diri ini tidak diberikan kepada kita, dan oleh karena itu kita harus menciptakan diri kita sebagai suatu karya seni.[20] Stylisasi diri dalam praktik-praktik Yunani (seperti mengatur seksualitas pribadi, hubungan perkawinan, diet, dsb), tidak didiktekan oleh hukum-hukum universal, di mana tindakan yang bertentangan dengannya dianggap dosa, melainkan dipilih secara estetis untuk memberi eksistensi diri seseorang suatu bentuk yang luhur dan terhormat.[21] Lebih ekstrem, Foucault menolak semua model baku dengan maksud menciptakan sesuatu yang radikal baru. Artis seperti ini tidak puas dengan stylisasi diri. Ia masih selalu coba menemukan dirinya (FR, 42), menciptakan suatu cara hidup baru, sesuatu yang secara radikal lain. Ia harus menghasilkan sesuatu yang belum eksis dan kita tidak tahu tentangnya, bagaimana dan apa itu (suatu inovasi total).[22] Bagi Foucault, transformasi diri adalah sangat sentral bagi hidup filosofis. Proyek transendensi diri yang terus menerus mengungkapkan etika perfeksionis yang sama tentang penguasaan diri. Askese merupakan suatu latihan diri dalam aktivitas berpikir.[23] Penutup Ditinjau dari perspektif berpikir yang adalah konfrontasi pribadi kita dengan realitas di sekitar kita, filsafat pada setiap era berpikir sesungguhnya bersifat sangat kontekstual. Karena karya berfilsafat berarti mengarahkan seluruh diri kita kepada realitas atau apa yang saya amati, pikirkan dan tanggapi mengenai realitas sekitar saya. Namun konteks seperti ini adalah konteks yang melulu bersifat historis dalam kaitan dengan eksistensi manusia sendiri yang hidup dan bergerak dalam ruang dan waktu. Kita sungguh mengharapkan agar para pemikir generasi sekarang melihat konteksnya yang lebih mendalam dan berusaha masuk ke dalamnya demi membangun suatu dunia yang lebih aman, baik, tertib, benar, adil dan penuh damai. Dunia kita sekarang hampir seluruhnya diwarnai oleh banyak hal negatip yang merupakan lawan dari apa yang disebutkan di atas. Para mahasiswa filsafat adalah mereka yang hidup dalam situasi sini dan kini, yang sendiri mengalami dan menanggapi seluruh permasalahan hidupnya. Mereka juga memiliki keprihatinan khusus akan suatu dunia yang adil dan damai, suatu lingkungan ciptaan yang utuh dan menarik. Karena itu kita mengharapkan agar lewat pelbagai kegiatan diskusi, seminar dan tulis-menulis yang lebih menekankan konteks kehidupan, para mahasiswa kita semakin peka akan situasi sekitar, dan kiranya ini juga menjadi cerminan kepribadian mereka yang suka damai, adil dan memikirkan kebaikan bersama manusia. Kematangan dalam berpikir kiranya menjadi cerminan siapakah saya yang sebenarnya, dan kiranya kedewasaan saya dapat terungkap lewat sikap dan tindakan saya yang semakin manusiawi. Kiranya
melalui seluruh tindakan dan sikap hidup, kita sudah bisa menilai tingkatan kematangan para mahasiswa kita. Catatan akhir:
[1]
Konrad Kebung, Dasar-Dasar Filsafat dan Logika (ms), Ledalero, 2005, hlm. 32-33; diterjemahkan dari The Documents of Vatican II, ed. by Walter M. Abbott, SJ, ( Piscata-way, NJ: New Century Publishers, Inc., 1966), especially Decree on Priestly Formation , no. 15, hlm. 450). [2] Konrad Kebung, op.cit.,hlm. 36. [3] Ibid, hlm. 14. [4] Bdk. W. G. Hobbs, Who Needs Philosophers? dalam The Chronicle of Higher Education, 9 (20 January 1975), p. 254. [5] Fenemonologi adalah suatu sistem berpikir dalam Filsafat atau juga metode filsafat, dalam mana subjek membiarkan realitas berbicara kepadanya, atau dengan kata lain gejala dan realitas dibiarkan mengungkapkan diri sebagaimana adanya. [6] Plato: The Collected Dialogues, ed. Hamilton Cairns (Princeton: Princeton University Press, 1989 (cet.14). Juga Richard McKeon (ed), The Basic Works of Aristotle (New York: Random House Inc., 1941 (first published) [ cet. 32]. [7] Bdk. Konrad Kebung, Imam dan Filsafat: Peran Filsafat dalam Spiritualitas dan Karya Pastoral Imam dalam Frans Ceunfin & Feliks Baghi (ed), Mengabdi Kebenaran (Maumere: Penerbit Ledalero, 2005), hlm. 235-257, terutama hlm., 246-252. [8] Bdk. Plato: The Collected Dialogues, op. cit. [9] Richard Shusterman, Practicing Philosophy: Pragmatism and the Philosophical Life (New York dan London: Routledge, 1997), hlm. 17-19. [10] Ibid., hlm. 51 [11] Ibid., hlm. 24 [12] Bdk. Richard McKeon, The Basic Works of Aristotle, op. cit. [13] Aristotle, Nicomachean Ethics, terj. Martin Ostwald (Indianapolis: Bobbs-Merrill Educational Publ., 1980), cet. 19. [14] Bdk. karyanya Culture and Value (Oxford: Blackwell, 1980). Dari sekarang digunakan singkatan CV. [15] Bdk. R. Schusterman, op.cit., hlm., 21-22 [16] Bdk karyanya, Lecture and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief (Oxford: Blackwell, 1970). [17] Bdk. Paul Rabinow, The Foucault Reader (New York: Vintage, 1984), hlm. 374. [18] Ibid., hlm. 50. [19] Ibid., hlm., 341, 343 [20] Ibid., hlm., 348, 351. [21] Michel Foucault, Care of the Self (New York: Random House, 1988), hlm., 185. [22] Bdk., Shusterman, op.cit., hlm., 27 [23] M. Foucault, The Use of Pleasure (New York: Vintage Books, 1990), hlm., 9.
Anda mungkin juga menyukai
- Perpenpan Dan RB No. 35 Tahun 2012 TTG Pedoman Penyusunan Sop AP (f4) FinalDokumen63 halamanPerpenpan Dan RB No. 35 Tahun 2012 TTG Pedoman Penyusunan Sop AP (f4) Finalballerinna88% (8)
- UU 2 Tahun 2020 - Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 Menjadi UU PDFDokumen53 halamanUU 2 Tahun 2020 - Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 Menjadi UU PDFBetta Anugrah SetianiBelum ada peringkat
- Prinsip Penyusunan SOP Yaitu Sebagai BerikutDokumen2 halamanPrinsip Penyusunan SOP Yaitu Sebagai BerikutInto Hyasintus100% (1)
- Aku Abdi TuhanDokumen1 halamanAku Abdi TuhanAngger RaditeBelum ada peringkat
- Aku Abdi TuhanDokumen1 halamanAku Abdi TuhanAngger RaditeBelum ada peringkat
- Perpres Nomor 59 Tahun 2017Dokumen12 halamanPerpres Nomor 59 Tahun 2017Toni SupraptoBelum ada peringkat
- Kelas6 Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan 1048Dokumen158 halamanKelas6 Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan 1048Dio KrisantoBelum ada peringkat
- The Problem of Planning TheoryDokumen3 halamanThe Problem of Planning TheoryInto HyasintusBelum ada peringkat
- Pembangunan Destinasi Wisata Pesisir Pada Dasarnya Bukan Hal Yang Sederhana Sebab Ada Banyak Komponen Yang Terlibat Serta Wajib Untuk Dipertimbangkan Dalam PerencanaanDokumen2 halamanPembangunan Destinasi Wisata Pesisir Pada Dasarnya Bukan Hal Yang Sederhana Sebab Ada Banyak Komponen Yang Terlibat Serta Wajib Untuk Dipertimbangkan Dalam PerencanaanInto HyasintusBelum ada peringkat
- Kebijakan Sebagai Science Dan Pembuatan Kebijakan Sendiri Sangat Berbeda Namun Dapat Dan Wajib Untuk Saling MelengkapiDokumen2 halamanKebijakan Sebagai Science Dan Pembuatan Kebijakan Sendiri Sangat Berbeda Namun Dapat Dan Wajib Untuk Saling MelengkapiInto HyasintusBelum ada peringkat
- The Problem of Planning TheoryDokumen3 halamanThe Problem of Planning TheoryInto HyasintusBelum ada peringkat
- Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir BerkelanjutanDokumen2 halamanPerencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir BerkelanjutanInto HyasintusBelum ada peringkat
- Dalam Menjalani Proses Kebijakan Pengembangan Wisata Pantai UjungnegoroDokumen2 halamanDalam Menjalani Proses Kebijakan Pengembangan Wisata Pantai UjungnegoroInto HyasintusBelum ada peringkat
- Model Pertumbuhan NeoDokumen1 halamanModel Pertumbuhan NeoInto HyasintusBelum ada peringkat
- Pemerintahan Yang GagalDokumen3 halamanPemerintahan Yang GagalInto HyasintusBelum ada peringkat
- Perencanaan KebijakanDokumen4 halamanPerencanaan KebijakanInto HyasintusBelum ada peringkat
- Model Pertumbuhan NeoDokumen1 halamanModel Pertumbuhan NeoInto HyasintusBelum ada peringkat
- Exit StrategyDokumen1 halamanExit StrategyInto HyasintusBelum ada peringkat
- Visi MisiDokumen14 halamanVisi MisiInto HyasintusBelum ada peringkat
- Pembangunan Dan Pertumbuhan EkonomiDokumen1 halamanPembangunan Dan Pertumbuhan EkonomiInto HyasintusBelum ada peringkat
- SinergyDokumen2 halamanSinergyInto HyasintusBelum ada peringkat
- Perencanaan KelautanDokumen130 halamanPerencanaan KelautanInto HyasintusBelum ada peringkat
- Politik Vs Perencanaan PembangunanDokumen4 halamanPolitik Vs Perencanaan PembangunanInto HyasintusBelum ada peringkat
- 5 1 Perikanan Dan Kawasan Konservasi PerairanDokumen19 halaman5 1 Perikanan Dan Kawasan Konservasi PerairanInto HyasintusBelum ada peringkat
- Bab II Buku Putih - LBTDokumen18 halamanBab II Buku Putih - LBTInto HyasintusBelum ada peringkat
- Rang KumanDokumen7 halamanRang KumanInto HyasintusBelum ada peringkat
- (Tulisan) - (Kelola Kawasan Konservasi Laut Pusat Keunggulan Didirikan)Dokumen2 halaman(Tulisan) - (Kelola Kawasan Konservasi Laut Pusat Keunggulan Didirikan)Into HyasintusBelum ada peringkat
- Desentralisasidanotonomidaerahdiindonesiadraftfinaluploadx061112 121106020440 Phpapp02Dokumen34 halamanDesentralisasidanotonomidaerahdiindonesiadraftfinaluploadx061112 121106020440 Phpapp02Into HyasintusBelum ada peringkat
- Profil Desa SejahteraDokumen3 halamanProfil Desa SejahteraInto HyasintusBelum ada peringkat
- Negara PolisiDokumen1 halamanNegara PolisiInto HyasintusBelum ada peringkat