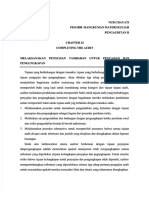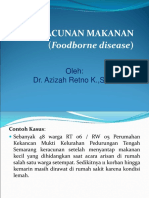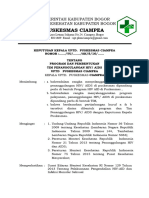Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Konteks Negara Hukum
Diunggah oleh
Kadek SudarmikaHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Konteks Negara Hukum
Diunggah oleh
Kadek SudarmikaHak Cipta:
Format Tersedia
1
HUKUM KONSTITUSI
IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM
OLEH :
I GUSTI NGURAH SANTIKA
I Gusti Ngurah Santika, SPd
PRAKATA Puji Syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga tulisan ini dapat diselesaikan sampai pada akhirnya berada ditangan pembaca seperti sekarang ini. Tulisan yang sedang saudara baca ini merupakan hasil revisi terhadap skripsi penulis untuk meraih gelar sarjana pendidikan (PPKn). Tentunya tulisan ini dapat terselesaikan, tidak lain dikarenakan belum adanya kesibukan, yang dapat digunakan untuk mengisi waktu luang di samping mengasah kembali kemampuan yang selama ini diperoleh di perguruan tinggi. Dengan adanya waktu luang yang tersedia tersebut, mungkin merupakan suatu kesempatan emas bagi penulis untuk belajar kembali dengan berusaha menulis hal-hal yang telah diketahui. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun di bangku kuliah, tidaklah banyak hal yang penulis ketahui berkaitan dengan apa yang nantinya disajikan dalam tulisan ini. Dengan demikian, tidak akan banyak yang mungkin dapat diberikan kepada pembaca, selain hanya sekedar mencoba untuk menyajikan sebuah tulisan singkat dengan segala kekurangan yang mungkin menyertainya kemudian. Tujuan utama dari penyebarluasan tulisan ini, tidak lain semata-mata merupakan upaya penulis, dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang akademisi, yang sedikit banyaknya telah memperoleh sekedar pengetahuan berkenaan dengan tulisan ini. Dengan demikian, janganlah berharap terlalu banyak terhadap apa yang terdapat dalam tulisan ini. Karena disadari atau tidak, apa yang kemudian tertulis di sini hanyalah merupakan sebuah ulangan yang mungkin tidak bisa disampaikan secara utuh dan lugas. Sehingga bisa saja setelah saudara membacanya, mungkin nantinya banyak hal yang belum bisa untuk ditemukan apalagi hendak untuk dimanfaatkan dalam tulisan ini. Bahkan ada suatu tulisan yang mungkin merupakan kekeliruan penulis, untuk memahami apa yang sebenarnya hendak dimaksudkan untuk kemudian disampaikan kepada pembaca. Maksud dari tulisan ini tiada lain adalah, hanya untuk sekedar memberikan imformasi berkenaan dengan masalah apa saja yang dibahas dalam tulisan di bawah ini. Oleh karena itu, tidak akan ditemui pembahasan yang luas dan mendalam terkait dengan materi yang dipaparkan tersebut. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis hanya mencoba untuk menghadirkan sebuah tulisan singkat dan sederhana, dengan menggunakan bahan-bahan serta materi kuliah yang dulunya didapat ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini, patut penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Bapak Drs. I Wayan Ngabuk Astika, MSi (alm), walaupun menyadari dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, namun dengan penuh semangat, dedikasi, keuletan
ii
I Gusti Ngurah Santika, SPd
serta kesabaran dan kebesaran hati beliau, untuk kemudian memberikan bimbingan dan bantuan, baik berupa nasehat, arahan sampai buku yang berhubungan dengan tulisan di bawah ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Untuk itulah, tulisan ini merupakan bentuk penghargaan penulis atas dedikasi beliau, terutama dalam pengabdiannya terhadap dunia pendidikan selama ini. Tidak lupa, juga ucapan terimakasih pernulis yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tinggi terhadap orang-orang yang selama ini berjasa kepada penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf yang mendalam terhadap para pembaca. Tulisan ini hanyalah merupakan suatu percobaan sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan berpikir, serta mengamalkan ilmu yang penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan yang pastinya tersimpan dalam tulisan ini. Untuk itu tegur sapa dari pembaca sangat penulis harapkan, dalam upaya perbaikan-perbaikan yang dilakukan ke depannya terhadap tulisan ini.
Karangasem, September 2013
Penulis
iii
I Gusti Ngurah Santika, SPd
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. BAB I KONSTITUSI A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi ............................................................. B. Pengertian Konstitusi ..................................................................................... C. Muatan, Tujuan dan Fungsi Konstitusi.......................................................... D. Klasifikasi Konstitusi .................................................................................... E. Nilai Konstitusi .............................................................................................. F. Amandemen Konstitusi..................................................................................
ii
1 16 21 27 49 52
BAB II UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 A. Sejarah Singkat Perjalanan UUD 1945 .......................................................... 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 (Revolusi). 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 (RIS) ..................... 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 (liberal) .............................. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 (Orde Lama).......................... 5. Periode 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998 (Orde Baru) ....................... 58 69 82 101 111 104
iv
I Gusti Ngurah Santika, SPd
6. Latar Belakang, Dasar Pemikiran Amandemen UUD 1945...................... BAB III SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA A. Teori Pembagian Kekuasaan ....................................................................... B. Pengertian Sistem Ketatanegaraan Indonesia ............................................... C. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen.......... 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ........................................... 2. Presiden dan Wakil Presiden .............................................................. 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ....................................................... 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)....................................................... 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)..................................................... 6. Mahkamah Agung (MA) ................................................................... 7. Komisi Yudisial (KY) ......................................................................... 8. Mahkamah Konstitusi (MK) ............................................................... BAB IV NEGARA HUKUM A. Negara Dan Hukum ..................................................................................... B. Pengertian Negara Hukum........................................................................... C. Tipe-Tipe Negara Hukum ............................................................................ D. Latar Belakang Timbulnya Konsepsi Negara Hukum............................ E. Prinsip-Prinsip Negara Hukum ..................................................................
v
139
157 172 182 182 207 272 309 326 339 356 372
412 429 436 436 463
I Gusti Ngurah Santika, SPd
F. Negara Hukum Indonesia........................................................................... BAB V SEKILAS BEBERAPA PASAL DALAM UUD NRI 1945 A. Amandemen Pertama Terjadi Pada Sidang Umum MPR, Tahun 1999 Disahkan 19 Oktober 1999 ......................................................................... B. Amandemen Kedua Terjadi Pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 18 Agustus 2000 ................................................................................................ C. Amandemen Ketiga Terjadi Pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 9 November 2001 ............................................................................................ D. Amandemen Keempat Terjadi Pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 Agustus 2002 .......................................................................................... Daftar Pustaka .................................................................................................... Biodata Penulis ....................................................................................................
466
489
537
585
623 640 688
vi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
BAB I KONSTITUSI A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi
Sebelum masuk ke dalam pembahasan UUD 1945, lebih tepatnya tentang perubahan atau amandemen UUD 1945, termasuk pula berkaitan dengan hasil dari perubahannya tersebut, alangkah baiknya apabila terlebih dahulu penulis mengajak pembaca untuk lebih memahami secara umum tentang teori konstitusi. Tidak lain disebabkan UUD 1945 merupakan konstitusi bagi bangsa Indonesia, yang pastinya juga memiliki berbagai persamaan maupun perbedaan, baik dalam hal teori sebagai sebuah konstitusi, yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecuali itu, dengan harapan akan diperoleh nilai-nilai yang kemudian menjadi standar, untuk selanjutnya dapat dikatakan bahwa suatu konstitusi dianggap sebagai pedoman utama, dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Standar-standar tersebut, merupakan prinsip-prinsip utama untuk selanjutnya memberikan suatu penilaian, tentang betapa pentingnya keberadaan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara, yang sekaligus juga kedudukannya sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dapatlah dikatakan bahwa konstitusi merupakan sumber hukum terpenting dan utama bagi negara. Pada zaman modern dapat dikatakan tidak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi (Chaidir,2007;29). Hal mana disebabkan adanya hubungan klausal antara negara dan konstitusi atau undang-undang dasar (Soemantri,1992;71). Hubungan tersebut timbul tidak lain disebabkan setiap negara memiliki konstitusi (Kelsen,2011;373). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Winarno, 2009;64). Begitupun dengan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara, yang kemudian dapat dipastikan memiliki UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi. UUD 1945 berfungsi sebagai konstitusi Indonesia sebelumnya telah disahkan oleh lembaga bernama PPKI, yang merupakan lembaga berwenang pada waktu itu untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian pada sidang yang pertama PPKI akhirnya berhasil mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini berarti konstitusi sudah ada sejak berdirinya sebuah negara, bahkan terkait dengan keberadaannya sudah dikenal seiring dengan perkembangan serta kompleksitas kehidupan bernegara.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
Namun, berkaitan dengan hal tersebut tentunya dalam pengertian konstitusi yang pertama dalam suatu negara sebagaimana dimaksudkan di atas adalah sebuah negara kota (city state) seperti Athena. Thaib dkk (2010;2) menyatakan bahwa pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404 S.M.) Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara. Oleh karena itu, dapatlah kemudian dikatakan bahwa konstitusi memiliki arti yang penting bagi suatu negara, meskipun fungsi konstitusi sebagaimana dimaksudkan seperti sekarang ini, baru lahir pada saat Amerika Serikat merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Dengan demikian, pada dasarnya undang-undang dasar/konstitusi merupakan wujud kehidupan daripada bangsa-bangsa yang telah beradab. Bahkan konstitusi tersebut sebagai dasar dalam menjalankan keberadabannya, yang selanjutnya didasarkan pada hukum tertinggi sebagai pedoman dalam rangka menjalankan pemerintahan di negara-negara tersebut. Samidjo (1985;231) berpendapat bahwa undang-undang dasar merupakan perwujudan daripada hukum tertinggi yang merupakan sumber bagi segala hukum yang lainnya. Jika pendapat Samidjo dikaitkan dengan Indonesia, maka akan diperoleh bukti/fakta bahwa negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ini, juga memiliki konstitusi/undang-undang dasar yang disahkan oleh PPKI sebagai lembaga berwenang untuk membentuk negara pada saat itu. Bahkan, dapat diikatakan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum dasar, sekaligus tentunya sebagai hukum yang kedudukannya tertinggi seperti dimaksudkan di atas. Karena sebagai hukum ia mengikat dan memaksa: (1) setiap lembaga negara, (2) setiap warga negara Indonesia, (3) setiap penduduk Indonesia, dan (4) setiap lembaga/organisasi kemasyarakatan (LSM, ormas, partai politik) (Hanapiah,2001;10) Lebih lanjut, ternyata konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sebuah bangsa, dikarenakan terdapat hal-hal mendasar yang kemudian tercantum dalam konstitusi tersebut sebagai hukum dasar yang tertinggi. Menurut K.C Wheare (2005;96) konstitusi pada hakekatnya, bukan sekedar hukum biasa. Ia adalah hukum dasar, ia menyediakan landasan untuk membuat dan melaksanakan hukum. Ia adalah prasyarat dari hukum dan peraturan. Konstitusi (atau UUD) merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan para warga (the citizen) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Marzuki,2009;19). Kecuali itu, ternyata UUD/konstitusi merupakan aturan dasar dalam penyelenggaraan negara, yang selanjutnya tidak hanya dipatuhi oleh warga negara, namun juga oleh setiap penyelenggara negara. Oleh karena itu, tentunya UUD memiliki sifat yang sebenarnya sama dengan norma-norma serta aturan yang lainnya, yaitu mengatur dan memaksa, bahkan sifat memaksanya terlihat dengan jelas lewat penjabarannya kembali dalam bentuk undang-undang sebagai noma pelaksana dari UUD tersebut. Dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
demikian, dapat dikatakan bahwa UUD memuat norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati (bersifat imperatif) (Rindjin,2009;267). Seiring dengan berjalannya waktu, setiap negara yang memiliki konstitusi atau UUD sudah pastinya akan berbeda, baik mengenai isi, maksud serta tujuan untuk diadakan/dibentuknya konstitusi tersebut. Bahkan hal yang mungkin paling mencolok terkait dengan adanya perbedaan antara satu konstitusi dengan konstitusi negara yang lainnya adalah berkenaan dengan materi muatan yang terkandung di dalamnya. Senafas dengan pendapat tersebut di atas, Manan dan Magnar (1997;145) menyatakan bahwa berbagai undang-undang (UUD) di dunia menunjukan berbagai perbedaan materi muatan. Perbedaan pokok dijumpai antara mereka yang menganggap konstitusi terutama dan hampir semata-mata sebagai dokumen hukum yang di dalamnya memuat peraturan-peraturan hukum dan mereka menganggap konstitusi sebagai semacam manifesto, sebuah pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita, atau, sebagaimana yang disebut podsnap, sebuah piagam negara (Charter of the land) (K.C Wheare,2005;49). Selain adanya perbedaan tersebut, sebagaimana dengan dimaksudkan di atas, maka perbedaan juga bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti bentuk negara, pemerintahan, sejarah negara, cita-cita negara, termasuk perbedaan ideologi di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Di samping itu tidak kalah pentingnya, pengalaman negara yang bersangkutan acap kali menentukan corak UUD (Asshiddiqie dan Manan,2006;2). Walaupun kenyataannya dapat dijumpai berbagai perbedaan muatan materi dalam setiap konstitusi di berbagai negara. Namun, pada dasarnya konstitusi sebagai dokumen formal, ternyata juga memiliki nilai dan kedudukan yang berbeda dengan dokumendokumen hukum lainnya. Diketahuinya perbedaan nilai dan kedudukan tersebut, sebenarnya dapat ditinjau dari kedudukan maupun fungsi konstitusi secara realitas yang diberikan di dalam negara itu sendiri, yaitu di negara tempat konstitusi tersebut berlaku. Jika dilihat dari kedudukannya, maka akan tampak bahwa hal-hal yang kemudian diatur dalam konstitusi memiliki nilai yang kedudukannya jauh lebih tinggi/luhur, apabila dibandingkan dengan hal-hal yang diatur dalam dokumen hukum lainnya. Dengan perkataan lainnya, isi konstitusi tersebut merupakan hal-hal yang kedudukannya paling penting dan mendasar, yang perlu diletakan di dalam konstitusi tersebut sebagai dokumen formal. Terkait dengan pendapat tersebut, lebih lanjut A.A.H. Struycken (dalam Hantoro,2009;1-2, Syahuri,2004;15, Huda,2010;149-150, Thaib,2010;57), menyatakan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
dengan tegas bahwa undang-undang dasar/konstitusi sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau; 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; 3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; 4. Suatu keinginan mengenai arah perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. Walaupun dari berbagai konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara dapat ditemui berbagai perbedaan, terutama berkaitan dengan kedudukan, fungsi maupun dalam materi yang kemudian diatur di dalam konstitusi tersebut. Tetapi perlu disadari bahwa pastinya ada berbagai kesamaan terhadap beberapa materi yang pada dasarnya bersifat pokok dan tentunya selalu terdapat di setiap konstitusi, sehingga negara yang memiliki konstitusi tersebut dapat selanjutnya dianggap sebagai negara konstitusional (constitutional state). Materi pokok sebagaimana dimaksudkan di atas yaitu: 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara; 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental(Soemantri,2006;60,Soemantri,1992;47,Thaib,2010;16,Syahuri,2004; 15). Untuk lebih mengetahui secara mendalam berkaitan dengan materi undang-undang dasar/konstitusi sebagaimana dimaksudkan di atas, maka akan dibahas lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas seperlunya. Masalah yang pertama untuk perlu dibahas dalam hal ini adalah hak asasi manusia, yang perlu untuk dicantumkan dalam konstitusi sebagai wujud daripada pengakuan bahwa negara tersebut adalah negara konstitusional (constitutional state). Hak asasi manusia berasal dari istilah droits de I home (Bahasa Perancis), human right (Bahasa Inggris), menslijke rechten (Bahasa Belanda), serta fitrah (Bahasa Arab). Ada yang menyebutkan bahwa hak tersebut sebagai hak fundamental
I Gusti Ngurah Santika, SPd
(Mahmud MD,2001;127). Dikatakan fundamental, dikarenakan hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang hanya dimiliki serta melekat pada manusia. Pada hakekatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu persamaan dan hak kebebasaan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakan (Ali,2010;146). Sebagai hak yang bersifat fundamental, tentunya seharusnya mendapatkan jaminan hukum yang pada dasarnya fundamental juga, konstitusilah sebagai aturan fundamental yang selanjutnya dapat melindungi hak asasi manusia dari kekejaman penguasa. Konstitusi modern diharapkan bisa merupakan jaminan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta paham welfare state, sekaligus memberikan perlindungan secara yuridis konstitusional (Thaib dkk,2010;6). Dengan adanya muatan materi pokok konstitusi yang mengatur hak asasi manusia seperti di atas, membuktikan bahwa adanya konstitusi setidak-tidaknya dalam tataran teoritis, minimal dapat menjamin bahwa hak-hak dasar manusia tidak akan dilanggar oleh penguasa. Namun, perlu diperhatikan dengan saksama bahwa berkaitan dengan konstitusi dapat dikatakan, yaitu tidak hanya dengan adanya konstitusi, maka hak asasi manusia akan terjamin dengan sendirinya. Untuk adanya perlindungan konstitusional bagi hak-hak asasi manusia, masih banyak syarat yang selanjutnya diperlukan oleh sebuah negara yang mengaku sebagai pelindung hak asasi manusia. Pendapat tersebut dinyatakan, disebabkan tidak mungkina dengan sendirinya suatu negara yang memiliki konstitusi, dapat kemudian disebut sebagai negara pelindung hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita harus melihat kembali isi konstitusi tersebut, apakah secara kenyataan aturan konstitusi tersebut memang memberikan jaminan hak asasi manusia sebagai ciri utama daripada negara hukum yang demokratis. Jadi, tidak cukup menjanjikan hak-hak demokrasi hanya melalui hukum tertulis, atau bahkan dengan suatu dokumen konstitusional. Hak-hak tersebut harus secara efektif dilaksanakan dan secara efisien tersedia bagi warga negaranya dalam prakteknya. Jika hal itu tidak terjadi, maka dalam hal ini sistem tersebut tidak demokratis, walau apa pun alasan yang dinyatakan oleh penguasanya, dan hiasan-hiasan demokrasi hanya sekedar fasada (permukaan) bagi aturan yang demokratis (Dahl,2001;69). Jadi, dapat saja apa kemudian yang diatur dalam konstitusi, ternyata berbeda dengan praktek di lapangan, yang pada dasarnya tindakan penguasa tersebut nyata-nyata bertentangan dengan isi (ketentuan) dari konstitusi itu sendiri, yang pada prinsipnya menekankan perlindungan hak asasi manusia. Namun, bukan berarti tidak ada gunanya, jika hak asasi manusia tersebut tertulis secara tegas (expressis verbis) dalam konstitusi. Namun, perlu ditegaskan kembali prinsip-prinsip konstitusional yang benar-benar dapat memberikan jaminan hak-hak asasi tersebut utamnya dalam realitas, pastinya hal tersebut akan dapat diketahui hanya dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan demikianlah, kita kemudian dapat menilai tindakan negara tersebut apakah sudah konstitusional atau tidak. Hal tersebut semata-mata sebagai evaluasi terhadap praktek-praktek konstitusional daripada suatu negara. Apakah konstitusi tersebut memang menganut gagasan konstitusionalisme atau tidak, karena pada dasarnya konstitusi tanpa gagasan konstitusionalisme, merupakan suatu pengingkaran terhadap maksud awal daripada dibentuknya konstitusi itu sendiri. Konstitusi terkait dengan hal tersebut seharusnya dapat memberikan suatu jaminan agar hak-hak asasi manusia senyatanya dapat diselenggarakan dan dinikmati oleh rakyat. Bahkan dalam hal ini perlu adanya kembali jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama oleh pemerintah sebagai penanggungjawab utama yang tentunya juga perlu untuk dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi. Artinya, konstitusi itu sebenarnya tidak boleh memberi pembatasan atas HAM atau menjadikan sebagai sisa dari kekuasaan pemerintah semata (Mahmud MD,2010;153). Apalagi yang kemudian menyebut dirinya sebagai suatu negara hukum yang bersifat demokratis. Tentunya negara hukum demokratis memberikan jaminan serta adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Karena pada dasarnya jaminan hak asasi manusia merupakan ciri khasnya yang paling utama sebagai suatu negara hukum, baik yang menganut konsep negara hukum formal maupun material. Oleh karena itu, asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan asas pokok, prinsip utama yang menentukan bahwa suatu negara merupakan suatu negara hukum atau bermaksud menegakan rule of law (Fadjar,2005;44). Negara hukum adalah suatu negara yang menentukan cara bagaimana hak-hak asasi dilindungi (Kusnardi dan Sarigih,2008;136). Namun, tidak berarti bahwa jaminan-jaminan HAM pertama-tama muncul dengan lahirnya pemikiran tentang negara hukum pada akhir abad ke -18, terhadap HAM tersebut telah ada sebelumnya (Tumpa,2010;51). Jadi, sebenarnya hak asasi manusia itu ada, dikarenakan oleh keberadaan manusia itu sendiri yang berkedudukan sebagai penyandang hak asasi tersebut. HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia (Muhtaj,2007;6). Karenanya, tidak ada yang bisa mengurangi atau mencabut hak asasi manusia, tidak konstitusi sekalipun (Lubis1993;x). Hak asasi manusia tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan, bahkan dengan hukum tertinggi sekalipun, karena hak asasi tersebut berasal dari harkat yang melekat pada setiap insan manusia (Nasution dkk,2001;90). Bahkan kekuasaan penguasa pun dibatasi oleh hak azasi ini (Soehino,1983;110). Pendapat tersebut selanjutnya membuktikan, bahwa hak asasi manusia merupakan bagian yang memang tak dapat dipisahkan dari eksistensi keberadaannya sebagai manusia yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi. Bukan kemudian malahan dilanggar dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
prosedural formal semata, tanpa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya jika hal tersebut dilihat secara substansial, terutama jika dihadapkan pada prinsip-prinsip negara hukum yang meletakan hak asasi sebagai ciri utamanya. Maka jika disuatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidaklah kemudian dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya (Asshiddiqie,2009;255). Oleh karenanya, negara seharusnya selalu berpedoman pada konstitusi dalam menegakan hak asasi manusia agar mendapatkan keadilan yang sejati. Tentu dikarenakan bahwa pada dasarnya kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi merupakan lambang negara hukum, yang di dalamnya mengatur cara-cara kehidupan bernegara, seharusnya mampu menjamin hak asasi manusia. Dikarenakan disepanjang sejarahnya hak-hak asasi manusia memang akan selalu secara langsung berhadapan dengan penguasa yang memiliki kekuasaan dan sewaktu-waktu dapat mengancam hak-hak asasi tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa tersebut harus tetap dalam garis batas yang telah disyaratkan sebagai negara konstitusional (constitutional state), yang kekuasaan tersebut tentunya harus berdasarkan konstitusi. Bahkan, dalam hal ini penguasa tentu seharusnya tetap mematuhi konstitusi dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, dengan menjungjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap langkahnya. Dengan demikian, diharapkan tindakan penguasa tidak akan melanggar hak-hak asasi manusia. Hak-hak ini merefleksikan suatu tuntutan moral untuk perlakuan umum yang sama bagi setiap orang (Forstythe,1993;8). Untuk itu, perlu adanya suatu tempat guna meletakan hak-hak dasar tersebut, dengan tujuan utamnya agar hak-hak dasar tersebut tetap dihormati serta dijungjung tinggi dan juga tentunya selalu dilindungi oleh penguasa. Lebih lanjut tempat tersebut yang penulis maksudkan tiada lain adalah konstitusi yang pada dasarnya merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada awal dibuatnya konstitusi adalah tiada lain berfungsi untuk melindungi harkat dan martabat manusia dari penindasan penguasa, yang telah terbukti dalam lintasan sejarah, terutama dalam menjalankan kekuasaannya yang cenderung bersifat absolut serta melanggar hak asasi manusia, yang seharusnya hak-hak tersebut mendapatkan jaminan konstitusional. Berkaitan dengan hal tersebut, konstitusi merupakan peraturan-peraturan dasar yang membingkai batas-batas kekuasaan pemerintah dan memuat keharusan perlindungan HAM oleh negara (Mahmud MD,2010;269). Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang di manapun juga mereka berada, yang hakekatnya tidaklah dapat dihilangkan ataupun dimusnahkan dengan berbagai alasan apapun, bahkan dengan hukum tertinggi sekalipun. Dikarenakan berkaitan dengan sejarah hak-hak asasi itu sendiri ada, sebelum hukum tertinggi tersebut dibentuk kemudian. Hanya saja harus disadari bahwa dengan adanya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
hukum tertinggi tersebut adalah semata-mata sebagai bentuk daripada kesadaran rakyat, berupa suatu perlawanan terhadap penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang, untuk kemudian menjamin serta mengukuhkan keberadaan daripada hak asasi manusia, yang memang ada sebelum negara tersebut terbentuk. Sehingga, penyangkalan terhadap universalisme hak asasi manusia, merupakan penyangkalan daripada eksistensinya sendiri sebagai seorang manusia, yang telah ditentukan sebagai penyandang predikat untuk memiliki harkat dan martabat. Kecuali itu, dikarenakan juga bahwa hak-hak asasi fundamental tidak berubah baik waktu maupun tempat dan hak-hak asasi tersebut adalah hak dasar bagi pembangunan manusia (Abdussalam,2007;103). Hak asasi sebagai mana dimaksud di atas menurut Abdurrahman dan Syahrani(1978;118) merupakan suatu hak asasi setiap insan yang hidup di permukaan bumi ini untuk menikmati hak hidup, kemerdekaan dan keamanan bagi dirinya, sebagaimana yang telah diakui secara tegas dalam pernyataan Umum Hak Azasi manusia. Kode ini (Deklarasi HAM 10 Desember 1948, pen) tidak hanya memiliki sifat dilaksanakan secara universal, akan tetapi juga mencakup prinsip-prinsip yang bernilai di bidang-bidang yang tadinya tidak diperhatikan dalam konstitusi-konstitusi negara-negara Barat (Cassese,2005;xx). Dengan demikian, hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya (Trianto dan Tutik,2007;259). Oleh karena itu, pengingkaran atasnya tersebut berarti pula mengingkari terhadap martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah atau organisasi apa pun berkewajiban untuk mengakui dan melindunginya pada setiap manusia tanpa kecuali (Prinst,2001;8). Perlindungan hak asasi manusia merupakan wujud utama keberadaan konstitusi dalam lintasan sejarah yang pernah ada. Namun, bisa saja suatu negara yang tidak memiliki konstitusi, tetapi memberikan jaminan terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam prakteknya seperti negara Inggris. Lagipula di Inggris tidak terdapat suatu piagam yang secara terperinci mencantumkan atau menjamin kebebasan-kebebasan warga-warga-negaranya, yang biasanya disebut hak-hak azasi manusia (Hartono,1982;8). Sekalipun demikian hak-hak azasi manusia di Inggris selalu dihormati, tidak hanya oleh sesama warga negaranya, akan tetapi juga oleh pemerintahnya (Hartono,1982;9). Konsep demikian telah menggambarkan, bahwa hak asasi manusia memang telah ada sejak dikenal dengan namanya manusia itu sendiri, yang berkedudukan sebagai penyandang harkat dan martabatnya terutama dalam berhadapan dengan bahaya yang berpotensi untuk menghilangkan atau menghapus hak asasi manusia itu sendiri. Bahkan, bukti-bukti sejarah telah menunjukan, baik di negara-negara barat maupun di
I Gusti Ngurah Santika, SPd
negara-negara timur, hak asasi manusia rentan sekali terhadap penindasan/kekejaman, terutama jika hak-hak tersebut berhadapan secara langsung dengan kekuasaan penguasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia memiliki sifat yang universal, karena tidak hanya berlaku di negara-negara Barat saja, namun juga di negara-negara Timur. Yang dengan kata lain, semua bangsa dan semua orang akan menghormati hak-hak asasi manusia seandainya mengetahui tentang adanya dan bagaimanapun hak-hak dari semua orang tersebut tidak dicabut (Morgenthau,1990;127). Namun, ICCE UIN (2010;121) menyatakan bahwa sekalipun substansi HAM bersifat universal mengingat sifatnya sebagai pemberian Tuhan, dunia tidak pernah sepi dari perdebatan dalam pelaksanaan HAM. Hampir semua negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM. Seiring dengan perjalanannya ternyata konsep hak asasi manusia dipandang berbeda di antara berbagai negara, terkait dengan pengertian, konsep maupun pelaksanaan di lapangan, yang tentunya juga berimbas pada implikasi dari hak asasi manusia tersebut dalam kehidupan nyata. Perbedaan tersebut terjadi berkaitan dengan perjalanan sejarah daripada keberadaan negara-negara tersebut, seperti perbedaan konsep hak asasi manusia antara blok Barat yang dimotori oleh Amerika dan Eropa Barat dengan blok Timur yang dimotori oleh Uni Soviet dan negara-negara yang baru merdeka setelah perang dunia kedua. Dikarenakan dalam hal ini menurut Berten (2011;200) bahwa Bagi blok komunis hak-hak asasi manusia yang paling penting adalah adalah hak-hak sosial, sedangkan hak-hak individual paling banyak ditekankan oleh blok Barat. Menurut Dahl (2001;65) bahwa satu-satunya penyelesaian terhadap kontradiksi ini mungkin sebuah kode hak asasi manusia yang secara universal yang dilaksanakan di seluruh dunia secara efektif. Masih berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, maka untuk itu, mau tidak mau, kekuasaan perlu dibagi antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dengan tujuan agar dapat mempersempit celah dari penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya pembagian kekuasaan yang jelas tentunya hak asasi manusia tidak akan pernah terjamin. Adalah menjadi kebiasaan untuk membagibagi tugas-tugas pemerintah ke dalam trichotomy; yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif (Suny,1986;15). Dasar pemikiran doktrin Trias Politica sebelumnya pernah ditulis oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan oleh John Locke, dengan menyatakan bahwa yang membatasi penguasa yang absolut itu, bukan karena pemisahan kekuasaan melainkan hak asasi manusia itu sendiri (Latif,2009;24). Misi utama pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan, karena pada masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas
I Gusti Ngurah Santika, SPd
10
seolah tanpa batas (Chaidir, 2007;15). Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu di tangan Raja atau Ratu yang memimpin negara secara turun temurun (2006;11). Dalil yang kemudian terkenal dari Lord Acton dalam Budiardjo (2008;107) yang menyatakan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalagunakannya secara tidak terbatas pula (Power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely). Dengan, adanya pemisahan kekuasaan dengan jelas, maka kecendrungan seseorang untuk menjadi diktaktor akan dapat ditekan seminimal mungkin, paling tidak dalam tataran teoritis jaminan hak asasi memang memerlukan pemisahan kekuasaan yang ditentukan secara tegas dalam konstitusi. Bahkan, menurut Cassese (2005;27) bahwa setiap masyarakat yang tidak menjamin hak-hak asasi atau tidak menentukan pemisahan kekuasaan adalah sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Dalam hubungan ini jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu masyarakat yang modern dan terorganisasi, jadi lebih daripada hanya sebuah kesejajaran yang biadab dari pribadi-pribadi yang bertarung antara sesamanya. Sehingga hanya dengan membagi-bagi kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam konstitusi, yaitu dengan meletakannya pada beberapa tangan berbeda, yang memang ditentukan dengan tegas oleh konstitusi, berutujuan untuk dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Pada akhirnya diharapkan mampu melindungi hak asasi manusia sebagai suatu konsep yang mencirikan negara tersebut sebagai suatu negara hukum demokratis. Demikian pula halnya di USA, kewenangan konstitusi, lembaga pemisahan antara kekuasaan dengan konsep hak azasi, merupakan cerminan kehidupan politik (Depari dan MacAndrews,1995;149). Ajaran Trias Politica seperti halnya dengan mencegahnya adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan dan prinsip checks and balances guna mencegah adanya campur tangan antar badan tersebut adalah jaminan dalam ajaran Montesquieu bagi adanya kebebasan politik (political freedom) (Kusnardi dan Sarigih,1986;31). Gagasan bahwa suatu kekuasaan harus dibatasi dengan membagi-bagi dalam beberapa badan, serta adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus dijamin dalam konstitusi, dengan demikian barulah negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara konstitusional (constitutional state). Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances yang merupakan prinsip dasar dalam paham konstitusionalisme (Sjuhad,2009;54). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya paham negara berdasarkan atas konstitusi tidak dapat dipisahkan dari negara berdasarkan atas hukum (Manan dan Magnar,1997;104) yang di dalamnya mengatur
I Gusti Ngurah Santika, SPd
11
pembagian kekuasaan, yang tentunya menjamin hak asasi manusia sebagai prinsip utamanya. Intinya negara yang memiliki konstitusi sebagai negara berdasar atas hukum, juga di dalamnya melindungi hak asasi manusia, yang merupakan salah satu ciri negara hukum. Hak asasi manusialah, yang merupakan jiwa konstitusi tersebut, disebabkan tanpa hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, negara tersebut merupakan negara yang selanjutnya hanya tinggal menunggu waktu untuk datangnya otoritarianisme. Tentunya jaminan hak asasi manusia dapat terwujud dalam implementasinya dikehidupan nyata, apabila konstitusi mengatur pembagian atau pemisahan kekuasaan (separation or distribution of power) antara lembaga-lembaga negara. Dengan adanya jaminan hak asasi manusia, serta adanya pembatasan kekuasaan penguasa, dapatlah negara tersebut disebut sebagai negara konstitusional (constitutional state) yang menganut paham konstitusionalisme. Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga negara dengan fungsi normatif tertentu, yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia, serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan (Syahuri,2004;15) Tidak berbeda jauh dengan pernyataan di atas, Carl J. Friedrich (dalam Winarno,2009;65,Budiardjo,2008;171,Huda,2010;156, Syahuri,2004;37) menyatakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi. Oleh karena itu, penerapan konstitusi dapat dijadikan alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Dengan demikian, pembagian atau pemisahan kekuasaan merupakan syarat mutlak untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sehingga hak asasi manusia dapat terjamin (Mahmud dalam Yudhanta,2011;th). Asumsinya ialah bahwa peluang untuk menjadi tirani dan diktaktor dikurangi selama badan-badan pemerintahan legislatif dan eksekutif (dan yudikatif) dipisahkan baik dalam hal kelembagaan maupun personal (Rodee,2011;67). Kemudian dalam konstitusilah terlihat adanya pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, yang pada akhirnya mampu menjamin hak-hak rakyat sebagai sebuah perjanjian luhur yang mengikat tentunya. Dengan demikian, konstitusi pada dasarnya dibuat oleh rakyat sebagai wujud social contract yang bersifat mengikat, sehingga pada gilirannya hanya konstitusilah yang dapat membatasi tindakan rakyat, bukan penguasa yang hanya sebagai wakil rakyat. Fhaisal(2007;23) menyatakan konstitusi dilihat sebagai satu-satunya bagian bangunan negara yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
12
mempunyai hak untuk menghakimi dan mengatur tatanan masyarakat. Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapain tersebut (Asshiddiqie,2005; 18). Dengan demikian, rakyatlah yang menjadi tumpuan daripada keberlakuan suatu konstitusi, apalagi suatu negara yang menyatakan bahwa dirinya sebagai negara penganut demokrasi, yang pada dasarnya menghendaki kekuasaan rakyat merupakan sumber daripada kemauan negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan dalam sejarah pertumbuhan konstitusi-konstitusi modern seperti sekarang ini, realitasnya telah mampu meletakan dasar-dasar kehendak rakyat dalam konstitusinya masing-masing sebagai bentuk pernyataaan suatu negara yang memang menganut demokrasi konstitusional (constitutional democracy). Keberadaan konstitusi pada awal pertumbuhan negara-bangsa modern tidak lepas dari pengakuan adanya paham demokrasi, yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat (Isharyanto,2006;1). Demokrasi menjadi jaminan bahwa, kekuasaan dalam konstitusi merupakan delegasi dari rakyat sendiri sebagai pemegang kedaulatan, dalam arti yang sesungguhnya. Betapapun, demokrasi dilihat sebagai suatu prinsip keabsahan pemerintah vox populi, vox dei (suara rakyat suara Tuhan)(Feit,2001;12). Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat, yang kemudian kedaulatan tersebut dituangkan ke dalam bentuk konstitusi, sebagai wujud daripada gagasan kehendak rakyat untuk melindungi hak-hak asasinya dari penguasa otoriter, yang nota bene merupakan wakil daripada rakyat itu sendiri. Maka dikembangkanlah konstitusionalisme sebagai ciri pemerintahan dalam negara demokrasi (Sani,2007;31). Dimana pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara demokrasi adanya suatu jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan cara membatasi kekuasaan penguasa dalam bentuk konstitusi yang bersifat demokratis. Dengan demikian, konsep hak asasi manusia (human right), pembagian atau pemisahan kekuasaan (distribution or separation of power) dan demokrasi (democracy) memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, bahkan tidak dapat dipisahkan dengan konsep konstitusi yang menjadi landasannya. Kemudian berkaitan dengan demokrasi, Cangara (2009;63) menyatakan bahwa demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti pemerintahan. Kata itu berasal dari kata Yunani untuk Rakyat dan memerintah (Rodee,2011;59). Pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people) (Winarno,2009;92). Dengan demikian, dapat selanjutnya dikatakan bahwa konstitusionalisme yang dapat tercapai hanya dengan adanya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
13
perlindungan HAM dan bentuk negara demokrasi untuk dapat tercapainya negara hukum. Menurut Mahmud MD (2010;279) bahwa gagasan tentang HAM dan demokrasi itu kemudian menuntut sistem negara hukum yang demokratis, dengan sistem pemerintahan yang dapat mengimplementasikan prinsip tersebut, yakni adanya pemerintah yang kekuasaannya dibatasi dan harus melindungi HAM yang dituangkan di dalam sebuah konstitusi. Maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (constitutional government). Jadi constitutional government sama dengan limited government atau restrained government (Nurtjahjo,2006;42). Untuk selanjutnya berkaitan dengan konstitusionalisme, Andrews (dalam Latif,2009;98, Huda,2010;161, Chaidir,2007;19) mengemukakan untuk tegaknya konstitusionalisme pada umumnya bersandar pada tiga kesepakatan, yaitu sebagai berikut. 1. The general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government (kesepakatan tentang tujuan atau cita bersama tentang pemerintahan); 2. The rule of law or the basis of government (kesepakatan tentang negara hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara); 3. The form of institutions and procedures (kesepakatan tentang bentuk institusiinstitusi dan prosedur ketatanegaraan). Marzuki (2010;129) menyatakan istilah konstitusionalisme bukan padanan makna konstitusi. Konstitusionalisme bermakna; pemerintahan yang digaris batasi. Artinya, suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasi oleh konstitusi (Djafar,2010;151). Tentunya, walaupun pada kenyataannya suatu negara memiliki konstitusi, namun jika dalam konstitusi tersebut tidak terdapat pembatasan kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya, maka pada gilirannya akan menindas hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusian seharusnya mendapatkan perlindungan dari konstitusi, maka dengan demikian tidaklah dapat dikatakan negara tersebut sebagai negara konstitusional (constitutional state). Bahkan berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, maka Kusnardi dan Sarigih (2008;154) menyatakan bahwa di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, maka konstitusi mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Menurut Randireksa (2009;139) bahwa konstitusi adalah dokumen organik dari
I Gusti Ngurah Santika, SPd
14
pemerintahan, yang mengatur kekuasaan pilar-pilar yang berbeda sekaligus acuan batasan kewenangan pemerintah. Dengan demikian, tujuan utama yang diharapkan adalah hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Berkaitan dengan konstitusionalisme, Muhammad Yamin dalam Syahuri (2011;35) memberikan pengertian konstitusionalisme, yang terdiri dari tiga pengertian, yaitu. 1. Bahwa pengakuan dan deklarasi hak asasi manusia merupakan persyaratan mutlak bagi setiap deklarasi kemerdekaan suatu negara; 2. Kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat harus diselaraskan dengan keadilan; 3. Kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat tidak hanya perlu dicatat dalam istilah jelas, tetapi harus diwujudkan pula dalam pasal-pasal yang jelas di dalam undangundang dasar. Pembatasan kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara sebagaimana yang dimaksudkan di atas tersebut, menurut Padmo Wahyono dalam Hadi (2007;17), setidaknya harus meliputi 2 hal yaitu sebagai berikut. 1. Pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya, 2. Pembatasan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut. Pembatasan kekuasaan dalam arti isi mengandung arti, bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga-lembaga negara. Bahkan terhadap lembaga yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam usaha menciptakan tujuan negara, dalam hal ini pemerintah, masih mendapat pengawasan dari lembaga/ permusyawaratan rakyat. Pembatasan dalam arti kedua adalah pembatasan kekuasaan mengenai waktu kekuasaan itu dapat dijalankan. Hal ini berkenaan dengan masa jabatan masing-masing lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, dalam waktu-waktu yang telah ditentukan harus dilakukan penggantian atau pembaharuan si pejabat (Thaib dkk,2010;23). Hal ini tentu dikarenakan bahwa karena sifat dan hakikatnya, kekuasaan tersebut untuk dapat bermanfaat harus ditentukan ruang lingkup, arah, dan batas-batasnya. Untuk itu diperlukan hukum yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri dan hendaknya dipegang secara teguh (Soekanto,2009;207). Konstitusi sebagai pembatas kekuasaan menimbulkan makna bahwa sebagian hak individu di dalam masyarakat melalui persetujuan bersama untuk bernegara maka tujuan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
15
yang hendak dicapai adalah untuk mendapatkan perlindungan yang dikehendaki adanya suatu negara (Sunarno,2009;23). Hal ini jelas terlihat berbeda dalam konstitusi komunis yang menyatakan bahwa In fact, bourgeois constitutions in all their essence reflecting and protecting the division of society into classes and the class domination of exploiters start of course from the class antagonism of bourgeois society, but pass it by in silence and suppress it (Vyshinsky,1948;136). Dengan demikian, pada dasarnya konstitusi komunis hanya melindungi satu kelas yaitu kaum proletar, sedangkan untuk kaum borjuis harus dihancurkan, karena hanya dianggap sebagai kelas yang melakukan eksploitasi atau kelas yang bersifat menindas. Selain itu, karena masyarakat kelas kita penuh dengan terorisme, karena kelas penguasa terus mengeksploitasi, mengorganisasi, membujuk, dan menghukum dalam rangka mencapai tujuan-tujuan (Kurzweil,2004;114). Dengan demikian, di negaranegara komunis pada masa lalu gagasan konstitusionalisme seperti diuraikan di atas tidak dikenal. Sesuai dengan pandangan bahwa seluruh aparatur serta aktivitas kenegaraan harus ditujukan kepada tercapainya masyarakat komunis, maka kaum komunis menolak prinsip konstitusionalisme seperti yang dikenal di negara-negara demokratis (Budiardjo,2008;175). Sehingga, boleh dikatakan bahwa konstitusi negara komunis tidaklah dapat diartikan sebagai negara yang menganut gagasan konstitusionalisme, yang pada prinsipnya membagi kekuasaan ke dalam beberapa lembaga ataupun tangan yang berbeda dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Bahkan, sebenarnya perlindungan yang kemudian diberikan terhadap hak asasi manusia, tidaklah membedakan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya sebagaimana dimaksudkan di atas. Karena, menurut Syahuri (2004;34) bahwa konstitusi lahir sebagai tuntutan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai suatu keadilan. Namun demikian, bahwa konstitusi sangatlah penting dalam kehidupan suatu bangsa, karena di dalamnya terdapat berbagai hal yang selanjutnya mendasari kehidupan bernegara untuk dapat menjalankan aktivitasnya. Menurut Djokosoetono dalam sunarno (2005;27), melihat pentingnya konstitusi (gronwet) dari dua segi. Pertama, dari segi isi (naar de inhoud) karena konstitusi memuat dasar (gronslagen) dari struktur (inrichting) dan memuat fungsi (administratie) negara. Kedua, dari segi bentuk (naar demaker) karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang. Oleh karena itu, untuk menghindari kekuasaan yang bersifat absolut dari raja-raja terdahulu, maka konstitusi timbul seiring dengan kesadaran dan kehendak rakyat, untuk mengatur diri mereka serta dapat membatasi tindakan-tindakan penguasa, dan tentu selanjutnya rakyat sendiri terikat kepada konstitusi tersebut. Sehingga apa yang kemudian menjadi isi daripada konstitusi tersebut pada
I Gusti Ngurah Santika, SPd
16
dasarnya merefleksikan kehendak rakyat, serta menunjukan kedaulatannya di hadapan para penguasa yang menjalankan pemerintahan untuk mengemban amanat rakyat, bukan sebagai manusia yang berdaulat serta tak bisa diganggu gugat. Hal mana adalah sesuai sekali dengan pendapat dari Wheare (2005;9) yang menyatakan bahwa jika kita mengkaji asalmuasal konstitusi modern, konstitusi-konstitusi itu, tanpa kecuali, dalam prakteknya, disusun dan diterapkan karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru, yang berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka. B. Pengertian Konstitusi Menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Chaidir 2007;21,Tutik,2008;101) bahwa Perkataan konstitusi berarti pembentukan berasal dari kata kerja constituer (Perancis) yang berarti membentuk. Terkait dengan konstitusi yang dalam bahasa Inggris, dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi (Soemantri,1993;29). Sementara itu, istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataaan Belanda Gronwet. Dalam kepustakaan Belanda, selain gronwet juga digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Indonesia, wet diterjemahkan sebagai undang-undang, dan grond berarti tanah (Winarno,2009;67, Huda,2010;142). Maksud pemakaian istilah konstitusi ini adalah pembentukan suatu negara, menyusun dan menyatakan suatu negara (Aminnudin,2006;57). Dalam literatur, dibedakan antara constitutie dan gronwet dalam bahasa Belanda, atau konstitusi dan UUD dalam bahasa Indonesia. Konstitusi diartikan lebih luas daripada UUD, yaitu bahwa konstitusi terdiri dari konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis, dimana UUD merupakan konstitusi tertulis (Fatmawati,2010;49). Pendapat tersebut adalah sesuai dengan pernyataan ICCE UIN (2010;60) yang pada dasarnya menyatakan bahwa istilah konstitusi (constitution) dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Lubis dalam Syahuri (2004;30-31) menyatakan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu konstitusi tertulis (undang-undang dasar) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi).Terkait dengan pandangan ini, maka menurut penulis untuk sekarang ini telah diterima pandangan bahwa konstitusi dan undang-undang dasar memiliki makna yang sama bahkan dalam kenyataannya merupakan suatu pengertian yang selanjutnya dapat diterima secara umum. Penyamaan arti keduanya ini sesuai dengan praktik ketatanegaraan disebagain besar negara-negara dunia termasuk di Indonesia (Thaib dkk,2010;7). Senada dengan pendapat penulis di atas, Budiardjo (2008;169) menyatakan bahwa UUD adalah bagian tertulis dari
I Gusti Ngurah Santika, SPd
17
suatu UUD, sedangkan UUD memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, setiap UUD tertulis ada unsur tidak tertulisnya, sedangkan setiap UUD tak tertulis ada unsur tertulis. Lebih lanjut terkait dengan pengertian konstitusi, maka dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah preposisi yang berarti bersama dengan, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kemudian kata statuere mempunyai arti membuat sesuatu agak berdiri atau mendirikan/menetapkan. Dengan demikian bentuk tunggal (constitution) berarti menetapkan sesuatu secara bersamasama dan bentuk jamak (constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan (Tahib dkk,2010;8, Huda,2010;142, ICCE UIN,2010;60). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konstitusi memiliki arti yang sangat penting dalam pembentukan negara di samping tiga syarat lain seperti pemerintahan yang berdaulat, wilayah, dan rakyat. Karena, sebelum ada konstitusi tidak mungkin pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, tidak lain dikarenakan bahwa konstitusi mengatur ketiga syarat di atas sebagaimana sebuah negara berdiri. Sehingga dapatlah kemudian dikatakan bahwa konstitusi menjadi barometer dalam menjalankan kehidupan suatu negara, yang mampu mengarahkan bangsa tersebut mengenai apa yang hendak dicapai. Di mana dalam konstitusi tersebut juga diatur mengenai lembaga-lembaga negara, sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, walaupun terkait dengan pengaturan hubungan antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan yang lain, tentunya akan berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Bahkan, bisa saja untuk sekarang ini, dengan kompleksnya kehidupan negara berkaitan dengan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan negara, tidak mungkin hanya dapat mengandalkan ketiga lembaga negara tersebut. Namun, setidaknya untuk di setiap negara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif akan selalu berdampingan dengan lembaga negara pentingnya lainnya, asalkan konstitusi menunjuk dengan jelas. Eric Barendt dalam bukunya yang berjudul An Intoduction to constitutional lawmenyatakan bahwa: The constitution of a state is the written document or text which outlines the powers of its parliament, government, courts, and other important national institution (Syahuri,2004;30, Chaidir,2007;33). Lebih lanjut pengertian yang tersebut di atas diberikan dalam buku lainnya menyatakan bahwa konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen yang tertulis yang secara garis besarnya mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan Yudikatif serta lembaga negara penting lainnya (Syahuri,2011;29). Sedangkan Joeniarto (1983;22, juga Mahmud MD dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
18
Marbun,2000;32) memberikan pengertian undang-undang dasar yaitu suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok atau dasardasar mengenai ketatanegaraan daripada suatu negara yang lazimnya kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal dan apabila akan mengadakan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat kalau dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan yang lain-lainnya. Tampaknya Joeniarto membedakan aturan hukum yang terdapat dalam konstitusi dengan aturan hukum yang ada di bawahnya. Lebih konkretnya, pembedaan beliau didasarkan pada prosedur perubahan konstitusi dengan prosedur perubahan peraturan yang lainnya. Suatu konstitusi pada hakekatnya adalah suatu hukum dasar yang pada prinsipnya merupakan dasar bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Karena tingkatannya yang lebih tinggi, dan juga menjadi dasar bagi peraturan-peraturan hukum lainnya, maka pembuat konstitusi menetapkan perubahannya tidak mudah, dengan maksud agar tidak mudah orang mengubah hukum dasarnya (Tutik,2008;112). Memang seharusnya perubahan konstitusi dengan peraturan yang kedudukannya berada di bawahnya akan berbeda. Tidak saja karena konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Selain itu, karena didasarkan dari bentuk konstitusi yang berbeda dengan peraturan-peraturan lainnya dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Lebih tegas lagi dalam masalah ini, Kelsen (2011;180) menyatakan adanya bentuk khusus bagi hukum konstitusi atau bentuk konstitusional adalah disebabkan oleh konstitusi material. Jika ada bentuk konstitusi, maka hukum konstitusi harus dibedakan dari hukum biasa. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa pembentukan, dan itu berarti pengundangan, perubahan, dan penghapusan hukum konstitusi adalah lebih sulit dari pembentukan, pengundangan, perubahan, dan penghapusan hukum biasa. Ada prosedur khusus, bentuk khusus bagi pembentukan hukum konstitusi, yang berbeda dari prosedur pembentukan hukum biasa. Ditinjau dari sudut politis, dapat dikatakan bahwa undang-undang dasar sifatnya lebih sempurna dan lebih tinggi daripada undang-undang biasa (Budiardjo,2008;184). Sebab jika saja dalam kenyataanya konstitusi sering diubah, akan berakibat pada turunnya wibawa konstitusi itu sendiri, bahkan kestabilan jalannya pemerintahan dipertaruhkan. Untuk itu, syarat-syarat perubahan yang berat diperlukan bertujuan untuk tidak dengan mudah mengubah konstitusi tanpa adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Tentu pada akhirnya semua sangat tergantung pada ada tidaknya dukungan politik. Terkait dengan pengertian konstitusi, dalam kamus Balck Law Dictionary seperti yang dikutip oleh Latif (2009;20, Chaidir,2007;35) menjelaskan pengertian konstitusi adalah the fundamental and organic law of a nation or state, establishing the conception,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
19
character, and organization of its government,as well as prescribing the extent of its sovergn power and the manners of exercise. K.C Wheare (2005;1) memberikan pengertian konstitusi, yaitu untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Sedangkan, C.F, Strong (2005;14-15) dengan mengutip pendapat dari James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga pemerintahan dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. Definisi yang diberikan oleh Strong dengan mengutip pendapat dari James Bryce tidaklah berlebihan, karena konstitusi merupakan hukum dasar dalam menyelenggarakan negara. Yang mana tentunya juga termasuk di dalamnya mengatur kehidupan rakyatnya sebagai pendukung utama daripada negara. Tanpa konstitusi, maka tidak dapatlah dibentuk aturan hukum, yang mampu menjadi dasar serta legitimasi dalam meletakan lembaga-lembaga negara serta memberikan tugas dan kewenangan kepadanya. Untuk lebih lanjut berkaitan dengan materi konstitusi akan diatur kembali dalam bentuk undang-undang organik yang kedudukannya berada di bawahnya. Dapatlah dikatakan bahwa pengertian konstitusi sebagaimana di atas, merupakan tinjauan konstitusi dalam arti materil yang mengutamakan perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi negara (Busroh,2001;89). Hal mana adalah sesuai sekali dengan pengertian konstitusi yang diberikan oleh E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law, yang pada dasarnya menyatakan konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut (Huda,2010;143, Budiardjo,2008;170, Kusnardi dan Sarigih,2008;139-140). Berikut ini merupakan beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai pengertian konstitusi yaitu sebagai berikut. 1. Pandangan Hermann Heller (staatslehre) dalam bukunya (staatrecht), professor Hermann Heller mengemukakan tiga pengertian konstitusi, yaitu sebagai berikut. a. Die politische verfassung als gesellchaftlichwirklichkeit. Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat; b. Dieverselbstandigte rehtverfassung. Konstitusi dilihat dari arti yuridis sebagai suatu kesatuan hukum yang hidup dalam masyarakat;
I Gusti Ngurah Santika, SPd
20
c. Die geschreiben verfassung. Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara (Thaib dkk,2010;9-10). 2. F. Lassalle dalam bukunya Uber Verfassungwesen, membagi pengertian konstitusi dalam dua pengertian, yaitu sebagai berikut. a. Pengertian sosiologis atau politis (sosiologische atau politische begrip). Konstitusi adalah sintesa dari faktor-faktor kekuatan nyata (dereele machtfactoren) dalam masyarakat. Jadi, konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut di antaranya: raja, parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dan lain-lain; itulah yang sesungguhnya konstitusi. b. Pengertian yuridis (yuridische begrip). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan (Daud Busroh dan Bakar Busroh,1991;73). 4. Sedangkan, Carl Schmitt dalam bukunya yang berjudul, Verfasungslehre, konstitusi dapat dipahami dalam 4 (empat) kelompok pengertian. Keempat kelompok pengertian itu adalah: (a) konstitusi dalam arti absolut (absolute verfassung begriff), (b) konstitusi dalam arti relatif (relative verfassung begrif), (c) konstitusi dalam arti positif (derpositive verfassung begrif), (d) konstitusi dalam arti ideal (ideal begrif der verfassung) (Asshiddiqie,2006; 126). Sebenarnya, sangat banyak pakar yang memberikan pandangan ilmiah tentang konstitusi, namun pandangan mereka mengandung esensi yang sama (Mahmud MD,2010;154). Oleh karena itu, menurut Ali (2010;76) bahwa pengertian konstitusi adalah lebih luas karena bersifat fundamental yang berkaitan dengan negara yang meliputi asasasas dasar, pranata-pranata, asas-asas hukum, norma-norma dasar, dan aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tentunya jika kita hanya menyatakan apa yang tertulis itu merupakan suatu konstitusi, maka kita hanya berpikiran tentang pengertian konstitusi dalam arti sempit saja. Hal tersebut tidak lain dikarenakan adanya aturan dasar yang tidak tertulis, namun dalam kenyataannya tidak kurang pentingnya dengan konstitusi yang tertulis, bahkan kadang-kadang lebih efektif dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan konstitusi yang tertulis. Bahkan, para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 menganut pandangan yang sangat luas terkait dengan pengertian konstitusi itu sendiri, yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
21
kemudian dinyatakannya kembali dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum di hapus. Di dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Biarpun aturan dasar tersebut tidak tertulis, namun bisa saja dalam praktiknya ternyata memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dengan konstitusi, yang kemudian biasanya disebut dengan konvensi ketatanegaraan (convention of the constitution). Menurut Kusnardi dan Sarigih (2008;139) bahwa konstitusi berarti hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar, sedang hukum dasar yang tidak tertulis disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan yang dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Sedangkan untuk pengertian sama, namun dalam kata yang berbeda diberikan oleh Wheare (2005;185) tentang tradisi adalah aturan yang mengikat, aturan perilaku yang dianggap wajib oleh mereka yang peduli dengan berjalannya konstitusi. Dengan demikian, pengertian tradisi yang diberikan oleh Wheare memiliki makna yang sama dengan konvensi. Budiardjo (2008;179) berpendapat tentang konvensi ialah aturan perilaku kenegaraan yang tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan kenegaraan dan preseden. Bahkan, Konvensi-konvensi ketatanegaraan itu diakui sebagai sumber hukum yang penting dalam praktek (Asshiddiqie,2006;240). Dan perlu ditekankan bahwa konvensi sebagai sumber hukum tidak dapat dituntut didepan pengadilan untuk pelaksanaannya (Mahmud MD dan Marbun,2000;35). C. Muatan, Tujuan dan Fungsi Konstitusi Konstitusi sebagai aturan dasar dalam kehidupan penyelenggaraan bernegara, memiliki nilai yang sangat tinggi/luhur. Karena apa yang kemudian diatur di dalamnya merupakan nilai-nilai bersifat luhur dari suatu bangsa yang sebelumnya telah mendapatkan kesepakatan dari bangsa tersebut. Sehingga apa yang kemudian menjadi isi daripada konstitusi tersebut, dijungjung tinggi dan dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dengan patuh sebagai hukum tertinggi yang mengatur serta mengikat. Meskipun, dengan ketentuan bahwa isi konstitusi setiap negara berbeda, hal mana dikarenakan oleh adanya perbedaan-perbedaan ideologi, politik, sosial yang menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan negara dan bangsanya. Oleh karena itu, dengan berbagai variasi yang menjadi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
22
muatan materi dari konstitusi, tentunya juga akan berimplikasi terhadap implementasinya dalam kehidupan bernegara yang akan berbeda-beda pula. Hal mana sebenarnya adalah tergantung daripada tujuan-tujuan untuk diadakan konstitusi tersebut, yang mana tentunya juga akan berbeda antara negara yang konstitusinya liberal, sosialis, komunis dan lain-lain. Namun, menurut Mirriam Budiardjo (2008;177) dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, walaupun undang-undang dasar atau konstitusi berbeda namun secara umum dapatlah dikatakan bahwa biasanya suatu konstitusi memuat (isi) ketentuan mengenai soalsoal sebagai berikut. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif. eksekutif, dan yudikatif serta hubungan di antara ketiganya. UUD juga memuat bentuk negara (misalnya federal atau negara kesatuan), beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu UUD memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaraan yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya. Dalam arti ini UUD mempunyai kedudukan sebagai dokumen legal yang khusus. 2. Hak asasi manusia (biasanya disebut Bill of tersendiri). 3. Prosedur mengubah UUD (amandemen). 4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari UUD. Hal ini biasanya ada jika para penyusun UUD ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktaktor atau kembalinya monarki. Misalnya, UUD Federasi Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktaktor seperti Hitler. 5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Penulis berpendapat bahwa apa yang kemudian menjadi isi daripada konstitusi seperti apa yang terdapat dalam tulisan Mirriam Budiardjo tersebut, merupakan standar minimum materi muatan yang memang terdapat dalam konstitusi-konstitusi modern seperti sekarang rights kalau berbentuk naskah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
23
ini. Untuk membuktikan pernyataan penulis tersebut, maka perlulah selanjutnya dibandingkan dengan sebuah konstitusi, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka untuk itu tidak perlu jauh-jauh guna membuktikannya, dapatlah selanjutnya kita bandingkan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dalam kenyataannya, juga terdapat hal-hal mengenai muatan konstitusi seperti yang disebutkan di atas. Misalnya saja tentang adanya pembagian kekuasaan lembaga lembaga negara antara legislatif (DPR) dalam Bab VII khususnya ketentuan Pasal 20, 20A, 21, 22 UUD 1945, Eksekutif (Presiden) dalam Bab III mulai ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945 UUD 1945, Yudikatif (MK dan MA) dalam ketentuan Pasal 24, 24A, 24C UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hubungan kekuasaan ketiga lembaga negara tersebut antara yang satu dengan lainnya. Mekanisme yang kemudian diterapkan UUD 1945 berkaitan dengan hubungan kekuasaan lembaga negara tersebut adalah pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan mengedepankan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), sehingga tidak ada lembaga yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang lainnya seperti di masa lalu. Di samping itu, dalam UUD 1945 diatur pula hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, 18A, 18B, 37 ayat (5) UUD 1945). Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan sistem desentralisasi, hal mana tentunya berbeda dengan bentuk negara yang menganut federalisme, dimana di dalam negara federal diadakan pembagian kekuasaan sedemikian rupa, sehingga terlihat sepintas adanya dua kekuasaan yang kedudukannya sama atau dengan kata lain akan terlihat seperti adanya negara dalam negara. Karena pada dasarnya kekuasaan dibagi sedemikian rupa antara negara federal dengan negara bagian, yang kedudukannya menunjukan sama-sama berdaulat, terutama dalam rangka melaksanakan kekuasaan masing-masing yang memang telah ditentukan secara tegas dalam konstitusi. Namun, untuk UUD 1945 bentuk negara yang dianut Indonesia adalah kesatuan, yang pada prinsipnya menempatkan kedudukan daerah berada di bawah pemerintah pusat, namun dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk selanjutnya mengelola masing-masing daerahnya yang betujuan agar rakyat di daerah dapat lebih cepat berkembang. Namun, kebebasan yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah pusat tidaklah semata-mata kebebasan tanpa batas, dikarenakan kebebasan yang kemudian dimiliki oleh daerah, haruslah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip NKRI. Maka, pemerintah pusat dalam hal ini masih memiliki kekuasaan untuk mengawasi daerah dalam bentuk executive review dan judicial review terhadap produk hukum daerah. Dengan demikian, apapun keputusan yang selanjutnya akan diambil oleh daerah tentunya kemudian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip daripada NKRI. Berkaitan dengan ketentuan hak
I Gusti Ngurah Santika, SPd
24
asasi manusia, sebagaimana dapat dilihat kembali dari hasil Perubahan Kedua UUD 1945 yaitu dalam ketentuan Pasal 28, 28A-J. Ketentuan tersebut semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, UUD 1945 telah menegaskan dirinya sebagai lembaga yang pada prinsipnya memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, sekaligus memberikan batasan terhadap kekuasaan penguasa. Sebagai sebuah konstitusi, UUD 1945 merupakan karya manusia biasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhannya pada saat itu. Namun paling tidak diharapkan konstitusi tersebut nantinya dapat mengakomodasikan kepentingan rakyat untuk jangka yang panjang. Namun, sebagai hasil dari manusia yang memiliki kepentingan politik (tidak lain dikarenakan dibuat oleh lembaga politik), tentunya juga bahwa UUD 1945 merupakan wujud daripada kepentingan-kepentingan politik dari para pembuatnya, yang terkadang kepentingan tersebut bisa saja bersifat jangka pendek. Sehingga untuk itu, UUD`1945 harus selalu mampu untuk mengikuti perubahan dan kebutuhan zaman serta tuntutan rakyat, maka dicantumkanlah di dalamnya ketentuan untuk melakukan perubahan. Ketentuan Perubahan UUD 1945 kemudian dicantumkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 37 UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut telah ditentukan lembaga mana yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan (MPR), beserta prosedur untuk melakukan perubahan agar kemudian dapat dikatakan sah. Lebih lengkap lagi, untuk sekarang telah ditegaskan satu prinsip sebagai sebuah komitmen bersama yang kemudian harus dipegang teguh, yaitu berkaitan dengan bentuk negara kesatuan, yang bukan merupakan objek daripada perubahan, jika seandainya saja melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945. Hal mana dapat dilihat kemudian dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, pembatasan ini merupakan ketentuan yang sangat bijak, sesuai dengan latar belakang kenyataan sejarah yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia dahulu, dimana pada saat itu Indonesia terpecah-pecah ke dalam beberapa negara bagian, akibat politik de vide et impera (memecah belah dan menguasai) Belanda yang berkeinginan membentuk negara serikat. Bahkan, sejarah sudah pernah membuktikan keinginan/hasrat rakyat akan persatuan melalui bentuk negara kesatuan, yang kemudian dikukuhkan kembali dengan Undang-Undang Sementara 1950 oleh para pemimpin bangsa. Berkaitan dengan ketentuan yang terakhir sebagaimana dimaksudkan di atas, bahwa UUD 1945 pada dasarnya merupakan sumber hukum tertinggi, sebagaimana dimaksudkan dalam Tap MPRS No XX/MPRS/1966, Jo.Tap MPR No. III/MPR/2000, Jo.UU No.10 Tahun 2004 yang kemudian diganti lagi menjadi UU No.12 Tahun 2011. Ketentuan tersebut merupakan sebuah pedoman dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang selanjutnya menegaskan kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertinggi.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
25
Tidak lain, dikarenakan kedudukan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang kedudukannya tertinggi, kemudian menjadi dasar hukum bagi peraturan yang kedudukannya berada di bawahnya. Dan ternyata jika dalam membentuk peraturan perundang-undangan sampai kemudian dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata dikemudian hari diketahui bertentangan dengan UUD 1945, maka harus dinyatakan batal dan tidak berlaku oleh MK. Selain sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat dikatakan bahwa isi konstitusi dimaksudkan sebagai suatu nilai-nilai bersifat luhur, karena sebagai wujud perjanjian tertinggi yang pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan, yang mana tujuannya tersebut tentunya akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Namun, diusahakan kemudian agar dapat menemukan tujuan konstitusi secara umum. Setidaknya setiap konstitusi memiliki tujuan yang memang telah ditentukan, serta tentunya disesuaikan dengan negara-negara tempat konstitusi itu berada dan berlaku. C.F Strong (2005;16, ICCE UIN,2010;60, Huda,2010;146) menyatakan bahwa tujuan singkat suatu konstitusi yaitu sebagai berikut. 1. Membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah; 2. Menjamin hak-hak yang diperintah dan; 3. Menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Kekuasaan merupakan hal yang sangat penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan terkait dengan kekuasaan telah dilembagakan dalam konstitusi, yang kemudian menjelma menjadi wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi prilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku (Budiardjo,2008;17-18). Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya (Soekanto,2009;230). Dengan demikian, besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, merupakan malapetaka jika suatu kekuasaan tidak dibatasi, dalam hal ini patut kemudian untuk dikutip pernyataan daripada Lord Acton dalam Budiardjo (2010;107) yang menyatakan bahwa Power tends corrupt to, but absolute power corrupts absolutely. Dengan adanya pembatasan terhadap kekuasaan penguasa, sehingga terjamin pemenuhan hak-hak warga negara, sebagai wujud tujuan daripada konstitusi suatu negara, yang menganut paham konstitusionalisme.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
26
Sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang tentunya suaranya juga merupakan hukum tertinggi (Vox populi supreme lex). Dalam negara demokrasi suara rakyat juga dapat diibaratkan sebagai suara tuhan (Vox populi vox dei) dapat tercapai. Selain memiliki tujuan, tentunya dapat dibedakan bahwa konstitusi juga memiliki fungsi-fungsi dalam kehidupan suatu negara-bangsa (nation-state). Berikut ini merupakan fungsi-fungsi konstitusi yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum tata negara Universitas Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. 6. Fungsi sebagai simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity). 7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation). 8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony). 9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. 10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat (social engineering atau social reform), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (Asshiddiqie,tt;28-29, Asshiddiqie,2009;164). Merupakan suatu keniscayaan untuk dapat menjadikan konstitusi berfungsi sebagaimana dimaksudkan oleh Jimly Asshiddiqie. Namun tentunya konstitusi yang merupakan puncak dinamika kehidupan berbangsa tidak akan berfungsi dengan baik
I Gusti Ngurah Santika, SPd
27
manakala tidak didukung oleh kekuatan-kekuatan yang ada dalam negara tersebut. Sehingga dengan demikian, suatu konstitusi tentunya akan sangat bergantung pula kepada kekuatan yang ada dan hidup di belakang konstitusi, yang tentunya akan memberikan jiwa, sehingga konstitusi sebagai hukum dasar benar-benar hidup dalam masyarakat (living law/constitution) (Kusnardi dan Sarigih,2008;139). Kemudian menjadi konstitusi yang tidak hanya diketahui oleh rakyat melainkan juga berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan jiwa konstitusi itu sendiri. Tentunya untuk dapat membumikan konsitusi itu sendiri kepada rakyat, seharusnya melihat ketentuan-ketentuan yang kemudian terdapat dalam konstitusi tersebut, apakah konstitusi tersebut demokratis atau tidak. Dikarenakan, tidak mungkin konstitusi yang tidak demokratis akan dapat hidup dan berkembang subur di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya mendambakan kehidupan demokratis. Untuk itu, diperlukanlah konstitusi yang demokratis untuk masyarakat demokratis. Maka setiap konstitusi digolongkan sebagai konstitusi demokratis yang tentunya harus menganut prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Menurut Tim ICC UIN (2010;67) bahwa konstitusi dapat dikatakan demokratis, apabila mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. 2. Mayoritas berkuasa dan terjamin hak minoritas. 3. Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu warga negara dan penduduk negara, sehingga dengan demikian identitas kolektif, tidak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak dasar orang perorang. 4. Pembatasan pemerintahan. 5. Adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah. 6. Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas. 7. Adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen. 8. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara meliputi: a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politica; b. kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
28
Dengan demikian, untuk dapat dinyatakan bahwa negara tersebut merupakan suatu negara hukum yang demokratis, setidaknya konstitusinya harus menganut prinsip-prinsip demokratis sebagaimana dimaksudkan di atas. Tanpa adanya kriteria yang jelas tentang bagaimana konstitusi dapat dikatakan demokratis, maka kita akan mengalami kesulitan terkait dengan bagaimana caranya dapat untuk kemudian membedakan antara negara konstitusional dengan negara yang hanya mendasarkan pada konstitusi semata. Sedangkan konstitusi itu sendiri pada dasarnya hanya menjadi alat legitimasi daripada penguasa untuk melakukan tindakan yang pada nyata-nyata sangat bertentangan dengan tujuan awal mula terbentuknya konstitusi. D. Klasifikasi konstitusi Dalam buku yang berjudul Modern Constitutions, K.C Wheare (2005;21-44) mengklasifikasikan konstitusi menjadi lima kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Written constitution dan unwritten constitution (konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis). Sebenarnya kuranglah tepat untuk selanjutnya membedakan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Tentu kurang tepatnya di sini dikatakan bahwa ada suatu negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis sama sekali atau dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara hanya berpedoman pada konstitusi yang berbentuk tertulis tersebut saja. Kekurang tepatan dari adanya pernyataan pertama dikarenakan oleh ketidak mungkinan bagi suatu negara, untuk menjalankan kehidupan bernegara yang kompleks seperti sekarang ini hanya mendasarkannya dengan suatu kebiasaan ketatanegaraan, atau yang kemudian lebih dikenal dengan istilah konvensi ketatanegaraan (convention of the constitution). Memang perlu untuk diakui bahwa konvensi ketatanegaraan sangatlah diperlukan dalam kehidupan bernegara. Tiada lain dikarenakan konstitusi itu tidaklah memuat materi secara lengkap yang dapat mencakup serta dapat mengatur semua aspek kehidupan bernegara. Dengan demikian, konvensi dapatlah melengkapi segala kekurangan yang ada pada konstitusi, terutama hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan pada saat pembentukan atau perubahan konstitusi, namun di sisi lain sangat dibutuhkan dalam praktik kehidupan bernegara sekarang ini. Namun, untuk kemudian dapat menyatakan adanya suatu konvensi ketatanegaraan tentunya diperlukan garis-garis yang jelas sebagai pedoman dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
29
rangka memahami, apakah sebenarnya aturan dasar tidak tertulis yang sebelumnya telah dipraktikan dalam kehidupan bernegara tersebut, merupakan konvensi ketatanegaraan atau tidak. Untuk itu, diperlukan suatu syarat yaitu berupa unsurunsur yang jelas dan tegas sebagai prasyarat utama untuk selanjutnya dapat dikatakan adanya konvesi ketatanegaraan. Berkaitan dengan konvensi ketatanegaraan, maka menurut Kusnardi dan Sarigih (2008;145) bahwa The convention of the constitution unsur-unsur utamanya adalah kelaziman (habits), tradisi-tradisi (traditions), kebiasaan-kebiasaan (customs), dan praktek-praktek (practices). Namun, terkait dengan adanya pembedaaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis sebagaimana dimaksudkan di atas, tentunya sudah menjadi sebuah kelaziman dalam dunia akademis untuk kemudian mengadakan suatu pembedaan antara konstitusi yang bentuknya tertulis dengan konstitusi tidak tertulis. Menurut penulis dikatakan bahwa Inggris, Israel, dan Selandia Baru tidak memiliki konstitusi yang berbentuk tertulis adalah suatu kekeliruan dalam memahami pengertian konstitusi yang dimaksud. Jika, singkatnya konstitusi diartikan sebagai dasar dalam rangka sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara, maka tentunya Inggris pun dapat dikatakan telah memiliki konstitusi, berupa dokumen-dokumen penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang kedudukannya dapat disetarakan dengan keberadaan konstitusi dalam lintasan sejarah seperti, Magna Charta 1215, Bill of Right1689 dll. Hanya saja semua dokumen tersebut terpisah atau dengan kata lain tidak dibukukan dalam satu naskah seperti konstitusi Amerika Serikat, melainkan kemudian tersebar dalam berbagai naskah yang tentunya memiliki makna tidak kalah pentingnya untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan demikian, naskah-naskah tersebut merupakan dokumen-dokumen yang sangat penting guna melengkapi kekurangan dari praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat dari J.G. Steenbeek (dalam Ridwan,2011;48) bahwa di samping peraturan perundang-undangan (UUD) tertulis ada peraturan-peraturan tidak tertulis yang melengkapi konstitusi tertulis. Keseluruhan dari peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis ini dinamakan hukum konstitusi. Oleh karena itu, sebaliknya dikatakan suatu negara memiliki konstitusi tertulis, jika ketentuan-ketentuan berupa aturan tentang penyelenggaraan kehidupan bernegara terdapat dalam satu naskah yang memang dibukukan. Sedangkan jika tidak memiliki satu naskah tertulis atau tersebar dalam beberapa tulisan, atau
I Gusti Ngurah Santika, SPd
30
tersebar dalam beberapa dokumen, maka dikatakanlah kemudian tidak memiliki konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis tersebut merupakan pedoman yang cukup jelas dijadikan sebagai sebuah instrumen bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara serta menjamin penyelenggara negara untuk tidak melenceng dari apa yang sebelumnya telah ditetapkan dalam konstitusi tersebut. Tetapi terkadang konstitusi yang disebut tertulis itu berupa suatu instrumen sangat- lengkap yang oleh para penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Pada kasus lain, konstitusi tertulis dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang para penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang biasa untuk mengembangkan konstitusi itu dalam aturan-aturan yang sudah disiapkan (Strong,2005;89). Dengan demikian, konstitusi memuat hal-hal yang hanya bersifat pokok dan mendasar terkait nilai-nilai yang kemudian menjadi norma dasar yang bersifat mengikat bagi semua komponen bangsa. Karena bersifat pokok dan fundamental itu maka konstitusi telah membuka berbagai kemungkinan untuk selanjutnya dapat mengikuti perkembangan jaman, sehingga diharapkan konstitusi tetap bernilai normatif. Seperti pernyataan di atas, konstitusi hanyalah merupakan sebagian daripada hukum dasar dalam suatu negara. Namun untuk dunia modern seperti sekarang ini, dimana gerak kehidupan suatu bangsa semakin dinamis, tidaklah menutup kemungkinan perubahan terjadi sangat cepat dan mendadak, sehingga tidak mungkin hanya mendasarkan kehidupan bernegara pada hukum tertulis saja yang dari waktu ke waktu cenderung bersifat kaku. Bahkan, sudah menjadi kebiasaan bahwa aturan tertulis itu selalu saja tertinggal oleh adanya praktik ketatanegaraan, yang mana terkadang disebabkan belum diaturnya hal-hal yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, dikarenakan memang terbatasnya pandangan manusia terhadap masa depan. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam konstitusi sebagai sebuah hukum dasar yang tertulis, perlulah kemudian untuk segera dilengkapi dengan hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi-konvensi ketatanegaraan). Namun, hukum dasar tidak tertulis tersebut tentunya dapat diterima oleh rakyat dengan penuh kesadaran sebagai dasar untuk menjalankan praktik ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya praktik ketatanegaraan tersebut haruslah selalu sesuai atau tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi demokratis yang melandasinya. Namun, perlunya sebuah aturan dasar yang tidak tertulis tersebut, tentunya kemudian dibatasi secara tegas agar dikemudian hari tidak melenceng dari tujuan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
31
semula untuk diadakannya aturan dasar tidak tertulis tersebut. Batas-batas yang dimaksudkan di sini tentunya adalah batas-batas yang memang dapat dibenarkan oleh konstitusi, atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang tertulis. Pentingnya aturan dasar yang tidak tertulis adalah untuk melengkapi aturan dasar yang tertulis. Bahkan aturan dasar yang tidak tertulis merupakan suatu keluwesan dalam usaha untuk kemudian mengimbangi cepatnya perubahan yang terjadi pada praktik ketatanegaraan dalam suatu negara tertentu. Hal mana disebabkan oleh seringnya suatu aturan yang bentuknya tertulis tersebut tertinggal dari praktik ketatanegaraan, yang menyebabkan setidaknya kita harus cepat menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi agar tidak menjadi penghambat pemerintahan untuk mencapai tujuan negara, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Aturan dasar tidak tertulis sangatlah diperlukan, dengan alasan jika kita tidak mau ketinggalan momen yang dipandang tepat untuk kemudian dapat menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan yang timbul. Dengan demikian, kita akan dapat mengurangi atau mencegah efek negatif dari kebutuhan yang tak terelakan tersebut dikarenakan belum adanya aturan dasar yang jelas untuk dapat digunakan. Namun, belum ada dasarnya untuk berbuat, tentunya menyebabkan pemerintah sulit bahkan mungkin gamang untuk mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan. Maka untuk itulah, perlu suatu kehendak berupa suatu kesepakatan bersama dalam bentuk penerimaan dan kepatuhan akan adanya suatu aturan dasar yang tidak tertulis, dimana aturan dasar tidak tertulis itu tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang bersifat demokratis adalah sangat mutlak diperlukan. 2. Flexible constitution dan rigid constitution (konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku). Mengenai klasifikasi konstitusi berdasarkan katagori fleksibel dan kakunya suatu konstitusi, setidaknya berkaitan dengan hal tersebut hanya akan dapat diperoleh kemudian, apabila klasifikasit tersebut berdasarkan pada prosedur perubahan konstitusi tersebut. Berkaitan dengan klasifikasi konstitusi apakah kaku atau fleksibel, maka Kusnardi dan Ibrahim (dalam Tutik,2008;112) menyatakan bahwa untuk menentukan apakah konstitusi tersebut bersifat plexible atau rigid dapat dipakai ukuran sebagai berikut: (1) cara mengubah konstitusi; dan (2) apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman (dinamis). Dikatakan bahwa suatu konstitusi adalah fleksibel bilamana dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi tersebut, prosedurnya sangat mudah bahkan saking
I Gusti Ngurah Santika, SPd
32
mudahnya dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi tersebut, dapat dilakukan hanya dengan undang-undang biasa. Yang mana undang-undang tersebut sebenarnya jika dilihat dalam prinsip negara hukum, terutama yang menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan, biasanya kedudukan undang-undang tersebut terletak di bawah konstitusi. Namun, dikarenakan konstitusi sendiri memang telah menunjuk undang-undang sebagai ketentuan yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu prosedur untuk melakukan perubahan konstitusi itu sendiri, maka pada dasarnya konstitusi sendiri telah menurunkan derajatnya. Dengan demikian, tentunya dalam negara yang menyerahkan perubahan konstitusi kepada badan legislatif dalam bentuk undang-undang biasa, sehingga akan terlihat seperti negara yang tidak memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang jelas, terutama kedudukan antara konstitusi dengan undang-undang biasa. Konstitusi yang bersifat fleksibel tentunya tidak memerlukan prosedur perubahan yang khusus misalnya dalam melakukan perubahan tidak dilakukan oleh dua lembaga negara yang berbeda kemudian melakukan sidang gabungan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi, yang disertai dengan syarat-syarat berat untuk sampai pada pengambilan suatu keputusan, yang mana agar keputusan tersebut merupakan keputusan yang sah seperti sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan. Bahkan, menurut Wheare (2005;25) konstitusi yang lentur karena dianggap sebagai konstitusi yang, karena tidak ada proses khusus yang diperlukan bagi amandemennya, mudah berubah dan sering diubah. Adanya ketentuan ini tiada lain bermaksud agar konstitusi yang mencerminkan dinamika kehidupan bangsa tetap dinamis, serta mampu untuk mengikuti perkembangan jaman dan mampu memenuhi tuntutan perubahan serta kebutuhan rakyatnya, seperti di negara Inggris, Israel dan Selandia Baru. Tidak lain, juga hal ini dikarenakan sangat mudah untuk kemudian menyesuaikan antara dinamika kehidupan bangsa, agar dapat selalu disesuaikan dengan praktik-praktik penyelenggaraan bernegara. Dimana tentunya akan dapat memudahkan para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas-tugasnya, karena hanya dengan sebuah undang-undang saja, ternyata dapat memberikan akses yang begitu luas kepada pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul kemudian hari. Bahkan yang lebih luar biasa lagi adalah hanya dengan undangundang tersebut, ternyata dapat melakukan perubahan terhadap konstitusi yang pada dasarnya merupakan aturan dasar tertinggi dalam negara. Paling tidak dapat katakan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
33
kemudian bahwa isi undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang sejajar dengan ketentuan konstitusi. Pemikiran daripada konstitusi fleksibel, didasari oleh suatu alasan yang logis, tidak lain dikarenakan jika hanya menunggu untuk merubah konstitusi dengan metode serta syarat-syarat yang sangat berat, tentunya akan membawa suatu resiko tersendiri, seperti menyebabkan terhambatnya pelaksanaan daripada tugas-tugas pemerintahan. Yang mana tugas-tugas pemerintahan tersebut sebenarnya membutuhkan waktu yang mendesak dalam pengambilan keputusan agar permasalahannya dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Dikarenakan tidak adanya pengaturan yang dapat menunjuk dengan jelas dalam konstitusi, tentunya akan menyebabkan kebingungan serta kegamangan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara oleh penyelenggara negara. Namun, harus disadari bahwa setiap sistem tentunya akan membawa resiko atau dampak tersendiri, baik resiko yang bersifat negatif maupun yang positif, termasuk juga dalam hal ini adalah terkait dengan konstitusi yang sifatnya fleksibel. Resiko dari konstitusi yang bersifat fleksibel, dikarenakan dengan mudahnya untuk melakukan perubahan konstitusi tentunya akan berdampak negatif terhadap konstitusi tersebut. Seperti dapat saja menurunkan wibawa konstitusi dihadapan para penyelenggaraan pemerintahan (baik oleh legislatif yudikatif maupun yudikatif). Bahkan dengan jatuhnya wibawa konstitusi sampai menyebabkan kaidah-kaidah konstitusi hanya merupakan kaedah tertulis di atas kertas, yang bilamana harus selalu sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan penguasa, kemudian dapatlah dirubah hanya dengan sebuah undangundang yang dibuatnya sendiri. Sehingga hal ini tentunya bukanlah maksud daripada tujuan semula untuk dibuatnya sebuah konstitusi fleksibel yang memang memudahkan untuk konstitusi diubah, sehingga sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dalam merealisasikan tujuan negara. Namun dalam kenyataannya, kesempatan tersebut dipergunakan hanya demi untuk kepentingan penguasa semata. Bahkan, dengan seringnya perubahan terhadap konstitusi tersebut, tidak saja dapat menjatuhkan harkat dan martabat daripada konstitusi tersebut. Namun seringkali menyebabkan kerugian yang tidak kalah seriusnya, yaitu ketidakstabilan daripada jalannya pemerintahan merupakan pertaruhan utamanya. Sedangkan untuk dapat dikatakan bahwa suatu konstitusi bersifat kaku dikarenakan dalam melakukan perubahan diperlukan suatu prosedur yang pada dasarnya tidak mudah ditambah dengan persyaratan khusus, yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut, bahkan persyaratan tersebut dapat dikatakan adalah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
34
sangatlah berat untuk dapat melakukan perubahan. Misalnya dalam melakukan perubahan konstitusi, yang jika dilihat dari sudut pengambilan suatu keputusan, maka biasanya ditentukan syarat-syarat seperti diperlukan jumlah suara yang telah ditentukan dari berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan. Contohnya dalam melakukan perubahan dengan dua majelis dan dari kedua majelis tersebut dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi, tentunya harus melakukan suatu sidang gabungan dengan suatu persyaratan misalnya berupa 2/3 suara dalam kedua majelis tersebut harus menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi tersebut. Bahkan, untuk di negara-negara yang pada umumnya menganut sistem pemerintahan parlementer dimana konstitusinya menyerahkan perubahan kepada lembaga legislatif yang terdiri dari dua kamar maka usul perubahan terhadap konstitusi diajukan oleh kedua lembaga tersebut dengan persyaratan suara yang telah ditentukan. Namun setelah memenuhi persyaratan untuk kemudian melakukan perubahan, ternyata bukanlah kewenangan orang-orang dari dalam lembaga yang mengusulkan langsung yang selanjutnya akan melakukan perubahan konstitusi seketika itu. Dikarenakan biasanya lembaga pengusul daripada perubahan konstitusi tersebut terlebih dahulu dibubarkan, barulah kemudian diadakan pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan lembaga legislatif tersebut. Lembaga hasil pemilu yang diisi oleh orang-orang baru inilah yang kemudian berwenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi. Dengan demikian, terlihatlah perubahan konstitusi yang sangat sulit untuk dilakukan. Selain itu, tentunya berbagai pembatasan-pembatasan telah pula ditentukan dalam konstitusi secara jelas berkaitan dengan prosedur perubahan daripada konstitusi tersebut. Perubahan konstitusi yang dikatakan sulit sehingga bersifat kaku misalnya perubahan konstitusi melalui persetujuan rakyat yang biasa disebut dengan referendum, juga merupakan salah satu syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi. UUD yang kaku biasanya hasil kerja dari suatu konstituante yang dianggap lebih tinggi kekuasaannya daripada parlemen karena memiliki kekuasaan membuat UUD (pouvoir constituant). Oleh karena itu biasanya konstituante dibubarkan pada saat tugasnya selesai (Budiardjo,2008;194). Bahkan, dalam negara-negara yang berbentuk federal kosntitusi memiliki nilai dan kedudukan yang sangat tinggi, dikarenakan merupakan perjanjian antar negara-negara yang membentuk serikat, sehingga tentunya dalam melakukan perubahan kosnstitusi memerlukan dukungan atau persetujuan dari negara-negara bagian. Karena diasumsikan bahwa konstitusi merupakan suatu
I Gusti Ngurah Santika, SPd
35
aturan dasar, yang memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan aturan yang lainnya, maka diperlukan prosedur yang khusus untuk melakukan perubahan konstitusi tentunya dengan tujuan agar tidak terlalu gampang untuk dirubah oleh kehendak-kehendak politik yang kepentingannya hanya bersifat sesaat, tanpa memperdulikan kepentingan rakyat banyak yang seharusnya dijamin oleh konstitusi agar diutamakan. Dasar pemikiran yang melatar belakangi sulitnya perubahan konstitusi menurut Kelsen (2011;365) yaitu karena konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum nasional, maka kadang-kadang tampaknya konstitusi dikehendaki agar memiliki karakter yang lebih stabil daripada hukum-hukum biasa. Oleh sebab itu, suatu perubahan dalam konstitusi dibuat lebih sulit daripada pembuatan atau perubahan hukum-hukum biasa. Hal mana adalah sesuai dengan pendapat Prodjodikoro (1981;44) bahwa untuk membentuk dan mengubah undang-undang dasar ini hampir di semua negara di dunia, diperlukan suatu prosedur lain daripada untuk membentuk dan mengubah undang-undang biasa. Akan tetapi adanya kesulitan perubahan tersebut menurut K.C. Wheare (dalam Tutik,2008;119), dalam kenyataannya memiliki motif-motif tersendiri yaitu (1) agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar; (2) agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan; (3) agar dan ini berlaku di negara serikat kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri; (4) agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan. Namun, jika persyaratan terhadap perubahan konstitusi terlalu sulit tentunya akan menyebabkan kekakuan yang mungkin luar biasa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahkan konstitusi tersebut tidak akan dapat menyesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan suatu negara yang sebenarnya bergerak begitu dinamis. Hal ini juga akan berakibat menjadi penghambat terhadap jalannya pemerintahan, yang dalam realitasnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya mengalami hambatan yang datang, tidak hanya dari praktek ketatanegaraan di lapangan, namun juga datang dari konstitusi itu sendiri, yang semuanya itu tentunya bertentangan dengan tujuan awal mula dibentuknya konstitusi. Dapatlah dikatakan Indonesia sebagai contohnya negara yang memiliki konstitusi bersifat kaku. Tidak lain hal ini dapat terlihat dalam UUD 1945 setelah diamandemen, di mana
I Gusti Ngurah Santika, SPd
36
ditentukan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 37 UUD 1945 bahwa DPD dan DPR yang kemudian mengadakan sidang gabungan dengan nama MPR (Pasal 2 ayat (1) UUD 1945), baru kemudian melakukan perubahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945 (Pasal 37). Dan biasanya konstitusi-konstitusi negara federalah, yang merupakan simbol daripada konstitusi yang bersifat kaku. Tidak lain dikarenakan konstitusi tersebut merupakan ikatan-ikatan terbatas, dalam pembedaan antara bentuk negara tersebut dengan bentuk negara lainnya. Menurut hemat penulis, fleksibel atau kaku tidaknya suatu konstitusi tidak hanya pada prosedur perubahan namun pada kenyataannya di lapangan apakah konstitusi tersebut sering diubah atau jarang dirubah. Bisa saja, persyaratan dalam mengubah konstitusi sangat berat, namun dalam kenyataannya konstitusi tersebut sering diubah ataupun sebaliknya meskipun persyaratan untuk mengubah konstitusi sangat mudah, namun dalam kenyataannya konstitusi tersebut tidak pernah diubah. Hal ini tidak lain daripada politik hukum suatu negara, realitasnya bahwa konstitusi merupakan sebuah hukum yang terlahir dari kesepakatan politik. Jadi, kekuatan politik terbesarlah yang menentukan apakah perlu atau tidak suatu konstitusi diubah. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur perubahan konstitusi sangat ditentukan oleh konfigurasi politik dalam negara tersebut. Jadi, konfigurasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya sangatlah berpengaruh atau menentukan produk konstitusi dan perundang-undangan (Mahmud MD,2011;6). Walaupun persyaratan dalam melakukan perubahan dalam konstitusi sangat berat, namun dikarenakan dukungan politik, yang diperoleh untuk melakukan perubahan konstitusi sangat besar, maka kekuatan minoritas tidak akan mampu untuk menahannya. Sebaliknya, walaupun konstitusi mensyaratkan dalam melakukan perubahan, bukanlah tergolong persyaratan yang sulit, namun karena kekuatan politik mayoritas tidak mendukung untuk melakukan perubahan, maka niscaya konstitusi tersebut akan tetap seperti apa adanya. Dengan demikian faktor politik sangat menentukan terkait dengan ada atau tidaknya perubahan konstitusi. Tetapi setidaknya, persyaratan yang ditentukan dalam konstitusi tentunya juga memiliki peranan yang cukup penting, untuk kemudian menentukan diubah atau tidaknya konstitusi dengan cara yang mudah atau sulit.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
37
3. Supreme constitution dan not supreme constitution (konstitusi derajat tinggi dan konstitusi bukan derajat tinggi). Konstitusi derajat tinggi dikatakan apabila kedudukan konstitusi tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki posisi yang paling tinggi. Bahkan kedudukan konstitusi, tercermin kemudian dalam prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan agar selanjutnya tetap taat terhadap asas hukum. Seperti adanya prinsip umum pembentukan peraturan perundangundangan menyebutkan bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya (Syahuri,2004;19). Oleh karena itu, jika dalam kenyataannya ada suatu peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya kedudukannya berada di bawah konstitusi, ternyata benar-benar bertentangan dengan konstitusi dimaksud, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dinyatakan batal ataupun batal demi hukum. Hal mana adalah sesuai dengan pendapat Han Kelsen yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku, berdasar dan bersumber pada hukum yang kedudukannya lebih tinggi, hukum yang kedudukannya lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada hukum yang kedudukannya lebih tinggi lagi, dan demikian seterus sampai pada norma yang tidak ada kedudukannya lebih tinggi lagi. Sebab jika masih ada yang lebih tinggi lagi, maka norma hukum tersebut akan terus berjenjang sehingga tidak ada habisnya. Dengan demikian, kedudukan antara norma hukum yang lebih rendah harus selalui sesuai dengan norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi. Karena itu, tidak terdapat pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, begitu sebaliknya (Attamimi dalam Oesman dan Alfian,1991;83). Hans Nawiasky yang merupakan salah seorang murid Hans Kelsen juga berpendapat bahwa selain norma sebagaimana dimaksud di atas, ternyata norma juga berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar (Indrati,2007;44-45, Attamimi,1990;287, Winarno,2009;17), yaitu (1) Staatfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara); (2) Staatsgrungezet (Aturan Dasar Negara); (3) Formell Gesetz (Undang-Undang formal); (4) Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana & Aturan otonom). Sedangkan menurut Kansil dan Christine (2002;152) bahwa suatu undangundang dasar (atau konstitusi) pada hakekatnya suatu undang-undang, yaitu suatu
I Gusti Ngurah Santika, SPd
38
undang-undang yang derajatnya, dalam arti materiil, lebih tinggi daripada derajat undang-undang biasa. Untuk itu, para pembentuk peraturan perundang-undang yang telah ditentukan oleh konstitusi maupun oleh undang-undang yang ada di bawahnya agar tetap memperhatikan ketentuan konstitusi, sehingga apa yang kemudian dibentuknya benar-benar tidak bertentangan dengan konstitusi, baik berupa caranya/prosedur dalam membentuk peraturan perundang-undangan tersebut maupun isinya. Untuk di Indonesia dapat dilihat kembali terkait dengan kedudukan UUD 1945 adalah konstitusi derajat tinggi. UUD 1945 merupakan hukum dasar sekaligus juga merupakan hukum yang kedudukannya tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta menjadi pedoman utama dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawahnya. Pernyataan ini dapatlah dilihat kembali dalam undang-undang yang sebelumnya telah menegaskan kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertinggi seperti di dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, kemudian diganti dengan Tap MPR No.III/MPR/2000 kemudian diganti lagi dengan UU No.10 Tahun 2004 dan yang terakhir dalam UU No 12 Tahun 2011, yang pada dasarnya menempatkan UUD 1945 dipuncak dari segala peraturan perundang-undangan di NKRI. Penempatan UUD 1945 sebagai puncak dari segala norma, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman utama bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan bagian dari ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 7 1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
39
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (kursif penulis). Selain itu, agar kemudian benar-benar dapat dikatakan meletakan konstitusi sebagai peraturan yang memiliki derajat tinggi, maka didasari oleh pemikiran tersebut dipandang perlu membentuk suatu lembaga negara yang ditetapkan untuk bertugas menjaga serta mengawal agar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi (the guardian of the constitution) tidak dilanggar oleh peraturan yang ada di bawahnya. Bahkan, untuk sekarang di beberapa negara telah terlihat menguatnya peran konstitusi dalam kehidupan bernegara, yang selanjutnya terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas untuk menjaga dan menegakan konstitusi, sehingga kemudian tidak akan diselewengkan oleh penguasa. Diawali oleh Amerika Serikat dengan lembaga Mahkamah Agungnya yang berinisiatif untuk menjaga dan menegakan konstitusi dengan menafsirkan undangundang yang sebelumnya dibentuk oleh lembaga legislatif, kemudian menyatakan bertentangan dengan konstitusi. Hal itulah yang selanjutnya menyebabkan timbul suatu kesadaran akan pentingnya mekanisme pengujian peraturan perundangundangan terhadap konstitusi, agar nilai-nilai konstitusi tersebut tetap hidup dalam kenyataan. Bahkan, disejumlah negara juga telah dibentuk lembaga yang bertugas untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi yang berada di luar lembaga Mahkamah Agung (Supreme Court) seperti di Amerika Serikat (United States), yang kemudian lembaga tersebut diberi nama Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Kemudian terkait dengan keadaan di Indonesia terutama setelah adanya Perubahan UUD 1945 tepatnya pada Perubahan Ketiga ternyata lembaga Mahkamah Konstitusi diadopsi ke dalam UUD 1945 (Pasal 24C ayat (1)). Mahkamah Konstitusi (constitutional court) merupakan lembaga negara pengawal konstitusi (the guardion of the constitution), yang nantinya akan menjaga dan menegakan nilai-nilai luhur konstitusi, agar dikemudian hari tidak ada undangundang yang bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, semakin mengukuhkan kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, yang mana tentunya tidak boleh disimpangi dengan undang-undang yang berposisi di bawahnya. Memang sebelum adanya lembaga Mahkamah Konstitusi ini, pemikiran mengenai pentingnya nilai-nilai konstitusi agar tidak diselewengkan terutama oleh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
40
peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawahnya sebenarnya sudah memperoleh bentuknya, yaitu dengan cara melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Agung. Namun mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan pemikiran ini untuk dapat terakomodasi, yang tidak lain disebabkan, oleh karena tidak mendapatkan apresiasi dari penguasa, sehingga selanjutnya menjadi tertunda sampai dengan adanya Perubahan Ketiga UUD 1945, yang pada dasarnya menerima lembaga MK (Mahkamah Konstitusi) beserta kelengkapannya yaitu berupa kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan yang dimiliki oleh MK untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 (yudicial riview, constitutional review or toetsingrecht), pada dasar bertujuan untuk menjaga keselarasan antara norma undang-undang yang berada di bawah dengan UUD 1945 yang berada di atasnya, agar kemudian tidak terjadi konflik norma. Pemikiran ini juga di dasari asas hukum, yaitu aturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, terutama dalam ini adalah UUD 1945, hal mana adalah sesuai dengan dalil lex superior derogate legi infreori. Dari segi konsepsinya, apa yang terkandung dalam perkataan constitutional review itu jelas berkaitan erat dengan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the constitution). Prinsip ini dalam perkembangan sejarahnya berhadapan-berhadapan dengan doktrin kedaulatan parleman (sovereignity of parliament) atau supremasi parlemen yang berdaulat. Dalam sistem pengujian konstitusionalitas (constitutional review), terkandung pengertian bahwa yang supreme itu adalah konstitusi (the idea of the supremacy of the constitution), bukan parlemen (Asshiddiqie,2010;30). Konstitusi bukan derajat tinggi, dikarenakan isi (muatan/materi) dalam konstitusi tersebut tidak memiliki kedudukan yang istimewa, dalam peraturan perundang-undangan, tertutama jika kemudian dibandingkan dengan kedudukan dari peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dan dalam kenyataannya tidak adanya upaya sebagai mekanisme untuk menjaga dan menegakan konstitusi tersebut dari kemungkinan pelanggaran oleh peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Tentunya dalam hal ini, jika dikemudian hari ada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan nyata-nyata bertentangan dengan UUD, maka tidak akan ada lembaga negara yang berwenang untuk dapat memutuskan tentang konstitusionalitas dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dapatlah dicontohkan konstitusi Belanda, di mana kedudukan konstitusinya tidak dapat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
41
dianggap sebagai konstitusi yang derajat tertinggi. Dikarenakan di sana tidak diperbolehkan adanya hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar (toetsingrecht). Jadi, hakim di sana tidak memiliki kewenangan, untuk menilai suatu UU (constitutional review) yang bersifat umum abstrak, melainkan hanya menerapkannya di lapangan secara individual-konkret. Walaupun nantinya undang-undang tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UUD, yang sebenarnya merupakan dasar keberlakuan daripada undang-undang tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan pernyataan Attamimi (1990;301) bahwa pengujian oleh hakim terhadap wet dalam arti formal umpamanya, di negeri Belanda tidak dapat dilakukan karena wet tidak dapat diganggu-gugat (anschendbaar). Dasar pemikiran ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu produk legislatif yang sudah ketinggalan zaman harus disesuaikan, harus diubah atau dicabut. Yang paling wenang mengubah atau menggantinya adalah pembentuk undang-undang sendiri (Mertokusumo,2009;37). Bahkan menurut Soepomo (1954) hak mengkaji hanyalah terdapat di dalam negara yang berbentuk federal saja. Tidak lain dikarenakan bahwa negara-negara yang pada dasarnya tidak menganut sistem pengujian peraturan perundang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, merupakan negara yang sesungguhnya meletakan posisi lembaga legislatif sebagai pemegang kedaulatan (supremacy of parliament), bahkan merupakan cerminan serta wujud daripada kehendak rakyat yang berdaulat. 3. Unitary constitution dan federal constitution (konstitusi kesatuan dan konstitusi serikat). Berkaitan dengan klasifikasi antara konstitusi federal atau kesatuan, ketentuan ini di dasarkan atas hubungan-hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang sebelumnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi. Dikatakan konstitusi kesatuan, dikarenakan kekuasaan yang besar terletak di pemerintahan pusat, artinya keputusan apapun yang diambil oleh daerah untuk keputusan terakhirnya tetaplah berada pada pemerintah pusat. Terutama hal-hal yang tentunya berkaitan dengan kepentingan nasional dari negara tersebut, yang pastinya tidak mungkin dapat untuk diberikan kepada pemerintah daerah. Daerah memiliki kekuasaan, tentunya kekuasaan tersebut luas atau tidaknya adalah tergantung pada pemerintah pusat yang selanjutnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, kekuasaan daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk hal-hal tertentu dan dalam batas-batas tertentu. Sehingga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
42
tugas dan kewenangan daerah pada dasarnya sangatlah tergantung daripada kehendak pusat, dalam rangka pemberian tugas dan kewenangan untuk lebih lanjut mengatur daerahnya sendiri. Sehingga pusat dapat menentukan dengan metode dan mengenai urusan apa saja, yang kemudian diberikan pusat kepada daerah. Bisa saja diatur dalam undang-undang bahwa kewenangan pusat dirinci secara tegas dalam undang-undang dan menyerahkan kewenangan lainnya yang tidak ditegaskan oleh undang-undang kepada pusat, untuk kemudian diselenggarakan oleh daerah ataupun bisa saja sebaliknya. Biasanya bentuk hubungan pusat dan daerah yang dianut dalam bentuk negara kesatuan adalah dengan merinci kewenangan daerah satu persatu. Maksudnya tugas-tugas dari daerah dirinci sedemikian rupa, ialah dengan tujuan agar dapat mengurangi pengaruh daerah atas pusat. Dengan demikian, daerah hanya mendapatkan kekuasaan yang terbatas sebagaimana telah ditentukan dalam konstitusi maupun dengan bentuk undang-undang yang bertugas sebagai pelaksana konstitusi. Bahkan, kewenangan daerah merupakan penyerahan oleh pusat, yang selanjutnya sewaktu-waktu dapat saja dihapuskan oleh badan legislatif pusat. Dapat kemudian dikatakan bahwa tidak ada daerah yang bersifat negara dalam suatu negara berbentuk kesatuan, misalnya hanya ada satu konstitusi untuk seluruh negara, satu kepala pemerintahan, satu badan legislatif yang tertinggi walaupun di daerah bisa saja kemudian dibentuk badan legislatif. Hal mana adalah sesuai dengan pendapat Busroh (2001;64) yang menyatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Walaupun tentunya dimungkinkan untuk daerah diberikan kewenangan dalam membentuk peraturan daerah, namun sifat dari peraturan tersebut adalah terbatas dalam rangka menjalankan kewenangan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Namun, diingat bahwa kewenangan untuk membuat peraturan oleh daerah merupakan pemberian daripada pusat, sehingga sewaktu-waktu lembaga legislatif pusat dapat saja menghapus kewenangan daerah dalam rangka membentuk peraturan daerah. Tujuan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya adalah untuk efisiensi, yaitu dengan pemberian hak otonomi daerah yang merupakan wujud utama daripada desentralisasi. Namun, untuk keputusan terakhir harus tetap berada di tangan pemerintah pusat dalam berbagai bentuk pengawasan, baik bersifat represif maupun preventif. Untuk itulah, peraturan daerah yang kemudian dibentuk tidaklah bersifat final, dikarenakan sebagai negara yang berbentuk kesatuan, maka peraturan yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
43
dibentuk oleh daerah sebagai bagian wilayah kesatuan perlulah dijamin, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan, maka masih diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat oleh pusat. Bahkan, jika nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maupun dengan kepentingan umum, maka pemerintah pusat dalam hal ini tentunya dapat saja membatalkannya. Dapatlah dicontohkan, seperti negara Indonesia dalam UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 18, 18B, dan 18C yang pelaksanaannya dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU No. 12 Tahun 2008. Bahkan, konsep yang dianut oleh UUD 1945 dalam rangka pembagian kewenangan antara pusat dan daerah telah ditentukan untuk dibentuk suatu undang-undang yang selanjutnya menentukan secara tegas kewenangan pusat yang kemudian sisa kewenangan dari pusat tersebut merupakan kewenangan daerah. Dalam undang-undang otonomi daerah tersebut juga ditentukan secara tegas bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan dalam UUD 1945 tepatnya ketentuan Pasal 18 Ayat (6) memberikan kewenangan, untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain, yang tentunya bertujuan dalam rangka menjalankan kewenangannya baik yang diberikan oleh UUD 1945, maupun dalam undang-undang yang kemudian dijabarkan di dalamnya. Namun, sebagai sebuah negara kesatuan, diperlukan mekanisme yang seharunya dapat digunakan, untuk mengawasi peraturan yang sebelumnya dibuat oleh daerah, bilamana tentunya jika peraturan daerah tersebut menyebabkan pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum atau dengan konsep yang mendasarinya, terutama hal mana harus menyesuaikan dengan bentuk negara kesatuan. Oleh karenanya, adanya upaya pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut oleh pemerintah pusat, yaitu dengan pengujian baik oleh pemerintah (excutive review) yang dalam hal ini adalah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Di samping itu peraturan daerah dapat saja kemudian diperkarakan ke Mahkamah Agung (judicial review), sehingga jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ataupun kepentingan umum dapat dibatalkan oleh dua lembaga tersebut. Sedangkan, untuk konstitusi serikat adalah konstitusi yang di dalamnya mengatur hubungan-hubungan kekuasaan antara beberapa negara, yang di mana masing-masing negara tersebut memiliki kedudukan dan kedaulatannya masingmasing, yang mana memang sudah ditentukan dengan tegas dalam konstitusinya. Pada dasar negara-negara yang menjadi anggota dalam negara federal tersebut
I Gusti Ngurah Santika, SPd
44
tetaplah memiliki kedaulatan, hanya saja kedaulatan tersebut dibatasi sedemikian rupa dalam konstitusi, yaitu hal-hal apa saja yang sebelumnya diberikan oleh negara bagian untuk kemudian diselenggarakan oleh serikatnya. Misalnya saja pemerintah serikat memiliki kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri atau mengenai angkatan bersenjata ataupun dalam mencetak mata uang, sehingga ini berarti negara bagian telah menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah serikat dalam bidangbidang tersebut, yang mana biasanya telah ditentukan secara tegas dalam konstitusi. Dengan demikian, serikat tidak boleh mencampuri urusan negara bagian ataupun negara bagian juga tidak dapat campur tangan terhadap hal-hal yang telah diserahkan dan diselenggarakan oleh serikat. Walaupun kekuasaan dibagi dalam negara federal menjadi dua kekuasaan, yaitu antara serikat dan negara bagian seperti sebagaimana dimaksudkan di atas. Namun, biasanya telah ditentukan pula dengan tegas dalam konstitusi bahwa sisa dari kekuasaan serikat, akan diserahkan kemudian kepada negara bagian, seperti dalam bidang pendidikan, pajak dll, yang selanjutnya akan menjadi kedaulatan daripada negara bagian tersebut untuk menyelenggarakannya. Tujuan daripada pengaturan secara rinci tugas-tugas daripada serikat dalam konstitusi adalah untuk memperbesar kekuasaan pada negara bagian pada satu pihak, sekaligus akan mampu mempersempit kekuasan daripada pemerintah serikat dipihak lain. Namun, ada yang sebaliknya ditentukan dalam konstitusi dimana kekuasaan negara bagian dicantumkan dengan tegas dalam konstitusi dengan cara merincinya satu persatu, kemudian sisa daripada kekuasaan tersebut tentunya berada di tangan serikat. Tujuan dirincinya satu persatu kekuasaan negara bagian adalah untuk memperbesar kekuasaan serikat disatu pihak, sehingga negara bagian tidak memiliki kekuasaan yang besar untuk dapat mempengaruhi pemerintah serikat, oleh karenanya serikat memiliki kekuasaan yang luas dilain pihak. Maka dari itu, menurut K.C Wheare dalam Budiardjo (2008;270) yang menyatakan bahwa prinsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Bahkan dalam negara federal, ternyata negara bagian memiliki perangkatperangkat yang hampir sama dengan yang dimiliki oleh pemerintah serikat, seperti kepala negara, konstitusi, hal inilah yang kemudian menyebabkan, seperti adanya suatu negara di dalam negara. Sehingga dapatlah dikatakan seperti terlihat adanya negara dalam negara, yang sama-sama memiliki kekuasaan serta kedudukan yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
45
hampir seimbang satu sama lainnya. Kelsen (2011;449) menyatakan bahwa masingmasing masyarakat hukum bagian, yakni federasi dan negara-negara bagian, bersandar kepada konstitusinya sendiri, konstitusi federasi dan konstitusi negara bagian. Namun demikian, konstitusi masyarakat federasi, yakni konstitusi federal, secara bersamaan merupakan konstitusi negara-negara bagian. Contoh dari negara negara serikat seperti India, Amerika Serikat,dll. 4. Presidencial executive constitution dan parlementary executive constitution (konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer). Untuk dapat mengetahui apakah konstitusi tersebut menganut sistem pemerintahan presidensial atau parlementer, maka perlu dilihat hubungan dua lembaga negara yang sebelumnya diatur dalam konstitusi. Seperti diketahui bahwa Montesqueu telah membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yang kekuasaan tersebut dipegang oleh lembaga-lembaga negara, yang masing-masing ditentukan secara terpisah, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam konstitusi yang menganut sistem pemerintahan parlementer, di sana telah ditentukan adanya hubungan-hubungan antara kekuasaan lembaga legislatif dengan kekuasaan lembaga eksekutif. Jika kita kembali menyimak dengan saksama, konsep pemisahan kekuasaan dari Montesquieu, maka dengan mendasarkan diri pada interaksi antara lembaga eksekutif dan legislatif, kita selanjutnya akan dapat dengan mudah membedakan antara konstitusi yang pada dasarnya menganut sistem pemerintahan parlementer ataukah konstitusi tersebut menganut sistem pemerintahan presidensial. Bilamana dalam konstitusi ditentukan bahwa kekuasaan lembaga eksekutif dikontrol langsung oleh badan legislatif, dalam arti kedudukan eksekutif tergantung daripada kehendak politik ataupun dukungan politik legislatif (political support), maka konstitusi tersebut menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer pertama kali lahir dan dipraktikan di negara Inggris. Yang dimana di dalamnya diatur bahwa kedudukan eksekutif (perdana menteri dan menteri-menterinya) tergantung pada dukungan suara dari parlemen. Dalam arti jika kabinet ataupun menteri secara perorangan tidak mendapat dukungan suara, karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen mengenai suatu kebijakan yang telah diambilnya, maka menteri ataupun kabinet tersebut harus mengundurkan diri. Dengan demikian, menteri-menteri bertanggungjawab kepada parlemen baik secara perorangan maupun secara bersama-sama (kabinet) mengenai kebijakannya. Selain
I Gusti Ngurah Santika, SPd
46
itu, biasanya perdana menterti dan juga menteri-menteri merupakan anggota legislatif, bahkan disyaratkan bahwa seseorang hanya mungkin dapat menjadi menteri apabila kemudian dia mendapatkan kursi pula di parlemen. Setelah di adakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen, kemudian akan terbentuk parlemen, sehingga barulah diadakah pembentukan eksekutif yang kemudian memilih anggota parlemen tersebut untuk selanjutnya menduduki jabatan menteri. Parlemen merupakan kunci dari sistem pemerintahan parlementer, karena setelah parlemen terbentuk, kemudian barulah dibentuk formatur kabinet oleh perdana menteri. Sedangkan untuk perdana menteri biasanya ditunjuk oleh presiden/raja dari partai politik mayoritas yang meraih kursi di parlemen dengan tujuan agar mendapatkan dukungan suara terbanyak dari parlemen, sehingga tidak mudah untuk kemudian dijatuhkan dengan mosi tidak percaya. Dalam sistem pemerintahan parlementer presiden/raja dapat saja membubarkan parlemen atas saran-saran dari perdana menteri, dengan alasan bahwa parlemen sudah tidak representasi lagi, atau tidak sesuai lagi dengan kehendak rakyat. Tentunya pembubaran parlemen oleh presiden/raja kemudian harus disusul pula dengan diadakannya pemilihan umum, untuk selanjutnya menanyakan kembali kepada rakyat, apakah terkait dengan pembubaran parlemen sebelumnya oleh presiden/raja dapat diterima atau tidak. Dengan demikian, lembaga parlemen hasil pemilu inilah yang akan menentukan kembali jawabannya apakah terkait dengan pembubaran parlemen terdahulu oleh presiden atau raja, apakah dapat dibenarkan atau tidak. Jika dalam hal parlemen yang baru dapat menerima keputusan terdahulu tentang pembubaran parlemen, maka kabinet akan berjalan terus seperti biasa. Namun, jika saja parlemen yang baru tersebut ternyata tidak menerima pembubaran parlemen terdahulu oleh presiden atau raja, maka bukan presiden/raja yang kemudian berhenti melainkan kabinetlah yang diharuskan untuk membubarkan dirinya. Perlu diketahui terkait dengan kedudukan presiden/raja dalam konsep sistem pemerintahan parlementer adalah the king can do no wrong, dalam arti raja tidak dapat berbuat salah, bahkan seandainyapun raja yang sebelumnya bersalah dalam melakukan tindakan berupa pembubaran parlemen, maka yang harus menanggung akibatnya adalah menteri atau kabinet menteri yang bersangkutan. Namun, telah menjadi suatu kebiasaan bahwa untuk selanjutnya jika terjadi konflik kembali antara kabinet dengan parlemen, maka perdana menteri atau raja, tidak mungkin dapat membubarkan parlemen kembali sampai kedua kalinya. Dengan demikian, terlihat jelas konsep saling mengawasi dan mengimbangi antara eksekutif dengan lembaga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
47
legislatif. Namun pada dasarnya titik kekuasaan pada sistem pemerintahan parlementer sebenarnya secara tidak langsung adalah pada partai politik, yang selanjutnya terlembagakan dalam parlemen untuk kemudian mewakili kepentingannya masing-masing. Selain itu, terkait dengan kedudukan kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer, maka presiden/raja sebagai kepala negara ternyata tidaklah memiliki kekuasaan riil/nyata, namun kedudukannya hanyalah merupakan simbol belaka, dalam arti hanya bertugas dalam acara seremonial. Di sini, terlihat jelas dekatnya hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif, bahkan karena dekatnya hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, menyebabkan sulit untuk kemudian membedakan antara organ eksekutif dan legislatif, terutama berkaitan dengan tugas masing-masing dari kedua lembaga tersebut. Karena selain menjadi anggota eksekutif, perdana menteri dan menterimenterinya yang duduk dalam anggota kabinet, ternyata juga diharuskan untuk kemudian duduk kembali dalam anggota parlemen. Sehingga dalam kegiatan sehariharinya menteri tersebut, terlihat pula ikut membimbing parlemen, berkaitan dengan tugas masing-masing seperti terlihat dalam pembahasan rancangan undang-undang. berkaitan dengan sistem parlementer, Ranadireksa (2009;106) berpendapat bahwa cara termudah untuk mengenali salah satu sistem pemerintahan dengan memperhatikan di mana letak obyek utama yang diperebutkan. Dalam sistem parlementer (sesuai dengan namanya), obyek utama yang diperebutkan adalah parlemen. Pemilu parlemen menjadi sangat penting karena kekuasaan eksekutif hanya mungkin diperoleh setelah partai kontestan pemilu berhasil meraih kursi mayoritas dalam parlemen. Kelemahannya adalah, jika sistem parlementer dengan sistem multi partai (lebih dari dua partai), dengan ditambah rendahnya kesadaran serta integritas partai politik dalam memposisikan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan nasional/bangsa dan negara, dapatlah menyebabkan ketidakstabilan jalannya pemerintahan. Apalagi jika sistem pemerintahan parlementer di damping dengan sistem multipartai, dapat lebih cepat menimbulkan jatuh bangunnya kabinet (krisis kabinet), karena adanya mosi tidak percaya daripada parlemen. Akibatnya sudah terang bahwa badan eksekutif acapkali tidak dapat menyelesaikan program/rencana kerja yang telah disusunnya. Selalu terjadi penggantian kabinet (dewan menteri) sehingga kebijaksanaan politik negara menjadi labil (Azhary,1986;68). Jika hanya sistem pemerintahan parlementer hanya dengan dilengkapi sistem dwi partai (dua partai), tentunya akan berpotensi menyebabkan electoral dictactorship, dalam arti dukungan suara yang banyak di lembaga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
48
legislatif yang di dapatkan oleh suatu partai politik, tentunya akan menyebabkan kemungkinan daripada pemerintahan kemudian menjadi sewenang-wenang. Karena pemerintah dapat saja melakukan apapun sesuka hatinya sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, dikarenakan tidak adanya kekuatan yang secara langsung dapat mengimbanginya, terutama oleh kekuatan oposisi yang biasanya dalam kedudukan minoritas. Terkait dengan kelemahan dari sistem pemerintahan parlementer, dapatlah kemudian diberikan contoh sejarah seperti yang dialami oleh Indonesia pada saat berlakunya konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950. Di mana pada periode tersebut (1950-1959), dengan adanya banyak mosi tidak percaya dari parlemen kepada kabinet, yang kemudian pada akhirnya menyebabkan kabinet jatuh, sehingga sangat berdampak buruk terhadap stabilitas politik, karena memang stabilitas politik tidaklah terjaga. Tidak lain juga dikarenakan oleh tidak mampunya satu partai politik untuk memenangkan suara mayoritas kursi di parlemen. Ditambah dengan adanya pengutamaan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara, seolah-olah partai politiklah yang kemudian menjadi sumber utama daripada instabilitas politik pada periode itu. Sedangkan untuk dapat dikatakan bahwa suatu konstitusi menganut sistem pemerintahan presidensial dikarenakan di dalam konstitusi tersebut, telah ditentukan bahwa presiden merupakan penyelenggara negara. Di mana presiden baik kedudukannya serta fungsinya dijadikan satu/tidak dipisahkan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Dengan demikian, presiden sebagai satu organ memiliki dua fungsi sekaligus yaitu baik sebagai kepala pemerintahan, maupun kepala negara. Sebagai kepala negara tentunya presiden merupakan simbol persatuan bangsa dan merupakan pusat upacara kenegaraan. Sedangkan kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan (yang biasanya dalam sistem pemerintahan parlementer dijabat oleh perdana menteri) yaitu sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dengan menteri-menteri yang kemudian dipilihnya. Dan perlu digaris bawahi juga bahwa kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan yang tentunya dalam hal ini tidak bertanggungjawab kepada lembaga legislatif dikarenakan pada dasarnya kedua lembaga negara ini memiliki kedudukan yang sejajar. Menteri-menteri pun tidak diperbolehkan untuk bertanggungjawab kepada parlemen/legislatif, melainkan bertanggungjawab hanya kepada presiden saja, dikarenakan kedudukan menteri-menteri itu adalah sebagai pembantu presiden, yang mana sebelumnya diangkat dan diberhentikan oleh presiden sendiri. Tidak
I Gusti Ngurah Santika, SPd
49
adanya pertanggungjawaban kabinet/menteri kepada parlemen, dikarenakan sebelumnya terkait dengan pembentukan formatur kabinet tidaklah ada campur tangan dari parlemen. Namun, tentunya presiden juga harus tetap memperhatikan perimbangan kekuasaan yang diperoleh sebelumnya di parlemen melalui partai politiknya, sehingga terlihat seberapa besar dukungan parlemen terhadap kedudukan presiden dalam membentuk formatur kabinet. Sekali lagi perlu ditegaskan di sini bahwa parlemen tidaklah dapat membubarkan kabinet, seperti dalam sistem pemerintahan parlementer terutama karena tidak mendapatkan dukungan suara dilembaga legislatif. Atau dengan kata lain pemerintahan akan berjalan terus tanpa terganggu oleh suara-suara lembaga legislatif, walaupun terlihat dengan tegas bahwa kabinet tidak mendapat dukungan dari parlemen. Presiden sendiri di satu pihak tidak dapat membubarkan parlemen seperti yang terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. Ketentuan ini merupakan suatu mekanisme dalam bentuk pengawasan dan perimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedudukan menteri adalah sangat jelas, dikarenakan tidak adanya rangkap jabatan antara menteri di dalam kabinet dengan parlemen, dikarenakan pada dasarnya kedudukan kedua lembaga negara tersebut adalah terpisah mengenai tugas dan fungsinya masingmasing. Bahkan tata cara untuk menduduki jabatan kedua lembaga negara tersebut adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya, walaupun sama-sama ditentukan untuk kemudian dipilih. Namun, dalam melaksanakan prosedur pemilihan orangorang yang akan duduk dalam lembaga tersebut dipilih dalam pemilihan umum oleh rakyat masing-masing secara terpisah, baik mengenai orang maupun waktunya. Yang menjadi masalah utama dalam sistem pemerintahan presidensial adalah adanya kecenderungan bahwa pemerintahan kemudian menjadi diktaktor. Bahkan terlihat tidak adanya pertanggungjawaban yang dapat dikatakan jelas terutama berkaitan dengan kegagalan jalannya pemerintahan kepada rakyat. hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kekuatan yang berimbang antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, akhirnya menyebabkan saling tarik menarik di antara kedua lembaga negara tersebut, yang mana tentunya tidak memiliki ujung pangkal yang jelas dalam memecahkan suatu masalah. Hampir setiap putusan yang diambil merupakan hasil tawar menawar antara badan legislatif dan badan eksekutif sehingga isi keputusan acapkali tidak tegas. Jarang sekali keputusan dapat diambil dalam waktu yang cepat, terkecuali dalam hal-hal yang bersifat darurat (keadaan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
50
darurat perang) tetapi dalam keadaan normal hal ini tidak mungkin bisa terjadi (Azhary,1986;67). Namun, tidak pula menampik daripada kelebihan yang merupakan bawaan dari sistem pemerintahan presidensil, seperti adanya stabilitas terhadap pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena disatu sisi pemerintahan (kabinet) tentunya tidak mungkin dapat dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen. Dikarenakan dalam menjalankan kekuasaannya masa jabatan eksekutif sudah ditetapkan dengan tegas dalam konstitusi dan tidak mungkin untuk dapat kemudian dijatuhkan melalui tindakan politik, kecuali setelah habisnya masa jabatannya. Yang tentunya dalam hal ini telah memberikan peluang yang cukup kepada pemerintah untuk kemudian merealisasikan program yang sebelumnya telah direncanakannya, tanpa merasa terganggu oleh parlemen. Selain itu, sistem ini juga membangun mekanisme checks and balances antara kedua lembaga negara tersebut sehingga akan mampu memperkecil kecendrungan terjadinya pemusatan kekuasaan hanya pada satu organ/badan. Contoh seperti UUD 1945 pasca amandemen yang menganut sistem pemerintahan presidensial, hal mana kemudian dapat diketahui pengaturannya dalam pasal-pasal UUD 1945, terutama berkaitan dengan hubungan antara Presiden dan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebenarnya menunjukan dengan jelas bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. E. Nilai Konstitusi Nilai konstitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai (values) sebagai hasil penilaian pelaksanaan norma dalam konstitusi dalam kenyataan praktik. Sehubungan dengan hal itu, Karl Loewenstein dalam bukunya Reflektion on the value of constitutions membedakan tiga macam nilai konstitusi atau the values of the constitution, yaitu normative value, nominal value, semantical value. Jika berbicara mengenai nilai konstitusi, para sarjana hukum selalu mengutip pendapat Karl Loewenstein mengenai tiga nilai normatif, nominal,dan semantik ini. Untuk itu maka akan diuraikan satu persatu mengenai nilai konstitusi dalam praktek. (Asshiddiqie,2006). Selanjutnya dikatakan oleh Karl Loewenstein bahwa setiap konstitusi akan terdapat dua aspek penting, yaitu aspek idealnya yang merupakan teori dan yang merupakan kenyataan sebagai praktek. Artinya bahwa sebagai hukum yang tertinggi, konstitusi itu
I Gusti Ngurah Santika, SPd
51
selalu mengandung nilai-nilai yang ideal sebagai das sollen yang tidak selalu identik dengan das sein atau keadaan yang sebenarnya dengan di lapangan (nyata). Untuk itu, apa yang tertulis dalam konstitusi perlu diverifikasi kembali bagaimana praktek ketatanegaraan berlangsung, apakah sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi. 1. Nilai Normatif (Normative Value). Jika dalam negara tersebut nilai-nilai yang berwujud menjadi norma-norma dalam konstitusi tersebut memang benar-benar dipahami, diakui, diterima, dipatuhi serta dilaksanakan dalam kehidupan kenegaraan, maka dapatlah dikatakan bahwa konstitusi tersebut bernilai normatif. Tanpa kecualian bahwa seluruh norma yang terkandung dalam konstitusi tersebut benar-benar menjadi pegangan, tidak hanya oleh penguasa saja namun juga oleh rakyat sendiri. Hal ini tentunya tercermin antara apa yang ditentukan dalam konstitusi dengan apa yang dilakukan oleh penguasa dan rakyat sungguh-sungguh mencerminkan norma-norma yang terdapat dalam konstitusi tersebut. Dapat dikatakan bahwa konstitusi ditaati dan dijungjung tinggi tanpa ada penyelewenangan sedikit pun (Tutik,2008;110). Dengan demikian, konstitusi tersebut benar-benar hidup dan mendarah daging di tengah-tengah masyarakat (living law/constitution), apa yang menjadi ketentuan konstitusi merupakan refleksi kehidupan kenegaraan yang sedang berjalan. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh warga negara dan penyelenggara negara selaku objek dari konstitusi tersebut, selalu patuh dan taat sesuai dengan jiwa dari konstitusi tersebut. Dapatlah dicontohkan misalnya dinyatakan dalam konstitusi adanya suatu jaminan untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara bebas di muka umum, tentunya norma konstitusi tersebut benar-benar dapat terwujudkan dalam kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk daripada hak asasi manusia. Dengan adanya suatu kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan mendirikan organisasi, baik yang bersifat politik, maupun sosial tanpa selanjutnya adanya pembatasan-pembatasan yang sifatnya hanya sebagai kedok saja dari penguasa, adalah merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya norma konstitusi secara normatif. Selain, karena memang disadari bahwa berkaitan dengan adanya batasan-batasan tersebut adalah perlu, namun batasan tersebut hanyalah diperuntukan sekedar untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan umum. Dengan demikian, pemberian hak-hak asasi tersebut di atas tentunya tidak bertentangan dengan tujuan semula daripada pemberian suatu hak tersebut berupa kemerdekaan untuk kemudian mendirikan organisasi baik yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
52
bersifat politik, sosial untuk tujuan menyampaikan pendapat seperti dimaksudkan di atas. 2. Nilai Nominal (Nominal Value). Konstitusi dikatakan bernilai nominal apabila dalam kenyataannya apa yang tercantum sebagai ketentuan dalam konstitusi ternyata sedikit berbeda dengan praktik yang terjadi dilapangan. Dengan kata lain konstitusi tersebut menurut hukum yang berlaku, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana, mestinya yaitu tidak memiliki kenyataan yang sempurna (Kusnardi dan Sarigih,2008;157). Dengan demikian, dapat saja terjadi kemudian baik secara keseluruhan ataupun sebagian, apa yang menjadi ketentuan (norma) berupa kemauan konstitusi secara jelas dinyatakan di dalamnya (karena tertulis), akan berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan, maka konstitusi tersebut akan bernilai nominal. Ketidak sempurnaan ini bisa terjadi dikarenakan adanya keadaan yang dipandang sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi pada saat itu, sehingga dimungkinkan untuk diadakannya suatu penyimpangan terhadap konstitusi, dikarenakan konstitusi di satu sisi tidak dapat mengantisipasi hal tersebut. Bahkan, bisa jadi ketentuan dalam konstitusi jelas-jelas berlawanan antara apa yang kemudian dipraktikan di lapangan oleh penyelenggara negara. Hal ini dapat dikaitkan dengan contoh di Indonesia pada masa revolusi, yaitu beberapa pasal dalam UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yang tersurat dengan jelas di dalamnya bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan adalah presidensial (quasi presidensial). Hal mana dapatlah kemudian dilihat dalam pasal-pasal (dulu Batang Tubuh) UUD 1945 sebelum diamandemen seperti ketentuan Pasal 4, 17,19,20 yang menyatakan dengan jelas bahwa sistem pemerintahan adalah presidensial (quasi presidensial). Namun, karena adanya ketentuan berupa Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang selanjutnya menyatakan adanya suatu perubahan terhadap sistem pemerintahan presidensial (quasi presidensial), kemudian menjadi parlementer, dengan tangunggjawab utama pemerintahan yang sebelumnya berada di tangan presiden selanjutnya beralih menjadi di tangan menteri baik secara bersama maupun untuk masing-masing berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, dalam kenyataannya terdapat ketentuan berupa pasal-pasal dalam UUD 1945, sepanjang yang pada dasarnya menyatakan sistem pemerintahan presidensial, kemudian berubahn menjadi bernilai nominal (tidak berlaku), karena semenjak adanya ketentuan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
53
tersebut sistem pemerintahan yang dianut berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. 3. Nilai Semantik (Semantical Value). Konstitusi yang bernilai semantik berarti konstitusi itu secara hukum memang berlaku tetapi sekedar untuk memberi bentuk atau melaksanakan kekuasaan politik. Atau dapat dikatakan bahwa konstitusi yang bernilai semantik adalah konstitusi yang norma-norma yang terkandung di dalamnya hanya dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan jargon, semboyan, ataupun gincu-gincu ketatanegaraan yang berfungsi sebagai pemanis belaka dan sekaligus sebagai pembenar dalam tindakan penguasa. Dalam setiap pidato, norma-norma konstitusi itu selalu dikutip dan dijadikan dasar pembenaran suatu kebijakan, tetapi isi kebijakan itu sama sekali tidak sungguh-sungguh melaksanakan isi amanat norma yang dikutip itu. Kebiasaan seperti ini banyak terjadi di berbagai negara, terutama jika di negara yang bersangkutan tersebut tidak bersedia mekanisme untuk menilai konstitusionalitas kebijakankebijakan kenegaraan(states policies) yang mungkin menyimpang dari amanat undang-undang dasar. Dengan demikian, dalam praktik ketatanegaraan, baik bagianbagian tertentu ataupun keseluruhan isi undang-undang dasar itu, dapat bernilai semantik saja (Asshiddiqie,2006;137). F. AmandemenKonstitusi. Konstitusi sebagai suatu kesepakatan politik yang ditetapkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bernegara pada waktu ia ditetapkan, terkadang seiring dengan berjalannya waktu, apa yang menjadi kebutuhan sekarang, tentunya akan berbeda pula dengan kebutuhan yang akan datang. Maka seiring dengan berubahnya kebutuhan suatu bangsa, tidak mungkin dapat membuat konstitusi yang sangat lengkap serta terus menerus dapat berlaku dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang sangat kompleks. Perlu dikehaui bahwa para pembuat konstitusi sadar bahwa, kendati telah diusahakan dengan sesempurna mungkin, namun layaknya karya manusia, konstitusi sudah pasti mengandung sejumlah ketidaksempurnaan (Ranadireksa,2009;131). Tidak lain dikarenakan kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti (Asshiddiqie,2009;327). Bahkan, kelemahan-kelemahan suatu konstitusi akan terlihat seiring dengan berjalannya waktu, terutama pada saat konstitusi tersebut dipraktikan dalam kehidupan bernegara, yang juga dikarenakan berubahnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
54
kebutuhan bangsa tersebut dalam mencapai tujuannya. Suatu konstitusi yang sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan bangsa, dalam menjalani praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya perlu untuk dirubah ataupun diganti. Yang mana dalam hal ini akan sangat tergantung pula dari intensitas kebutuhan bangsa tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk kemudian mencapai tujuan bangsa yang memang telah ditetapkan sendiri dalam konstitusi tersebut. Maka dirasa perlu untuk adanya suatu mekanisme tentang perubahan konstitusi, yang selanjutnya dapat dijadikan sebuah pegangan/pedoman dalam menjalani perubahan kehidupan bangsa dan negara, sehingga konstitusi tersebut tidak dimakan oleh perubahan zaman. Oleh karena itu, perubahan konstitusi, merupakan suatu keniscayaan untuk kemudian menjadikan konstitusi tersebut benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat (living constitution) (Kurnadi dan Sarigih,2008;139). Tanpa ada suatu perubahan, maka konstitusi itu sendiri akan menjadi suatu penghambat utama untuk mencapai masyarakat yang memang dicita-citakan, serta berpotensi menjadikan konstitusi sebagai salah satu penghalang, tercapai cita-cita yang sebelumnya diharapkan, bahkan sebenarnya cita-cita tersebut merupakan tujuan awal yang kemudian melatar belakangi (historical background) dibentuknya konstitusi tersebut. Untuk itu, perubahan konstitusi merupakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak dapat dihindarkan. Hal mana dikarenakan menyesuaikan konstitusi tersebut agar selalu sesuai dengan keadaaan sekarang, yang pada akhirnya dapat membuat konstitusi semakin hidup (living constitution) ditengah-tengah kehidupan bernegara, sehingga tidak hanya hidup dalam pernyataan (semantic value), namun juga dalam pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan (normative value). Perubahan konstitusi sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa pencabutan (repeal), penambahan (adition), dan perbaikan (revision) ini semua tergantung dari pilihan kesepakatan yang dipilih. Istilah lain perubahan adalah pembaharuan (reform). Jadi pengertian perubahan konstitusi dapat mencakup dua pengertian, yaitu: 1. Amandemen konstitusi (constitutional amendement). 2. Pembaharuan konstitusi (constitutional reform) (Syahuri,2004;44).
Terkait dengan pengertian dari perubahan atau amandemen UUD, mempunyai banyak arti. Amandemen tidak saja berarti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan dalam UUD tetapi juga mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
55
dalam UUD yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya (Chaidir,2007;59). Kata amandemen adalah serapan yang berasal dari bahasa Inggris, amandement, yang berarti perubahan. Sedangkan istilah perubahan sendiri berasal dari kata dasar ubah yang mendapat awalan per- dan akhiran -an. Secara etimologis, kata perubahan berarti hal (keadaan) berubah, peralihan, pergantian atau pertukaran (Maksudi,2012;99-100). Sedangkan, Radjab (2005;115) berpendapat dengan menyatakan bahwa amandemen merupakan perbuatan mengubah harus diartikan dengan mengubah konstitusi yang dalam bahasa Inggris adalah to amend the constitution. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Verandring (verandringan) in de Grondwetdengan demikian, mengubah suatu konstitusi berarti konstitusi menjadi lain atau berbeda dengan materi aslinya. Menurut John M. Echols dalam Tutik (2008;115) menyebutkan bahwa amandemen adalah amandemen yang dalam arti bahasa berarti mengubah undang-undang dasar. Untuk itu, terkait dengan UUD 1945 Perubahan, tidak meniadakan/tidak mengcoup UUD 1945. Untuk mempertahankan nilai-nilai kesejarahan, sehingga tetap dapat dikenali secara terus menerus oleh setiap orang dari generasi ke generasi. Perubahan merupakan tambahan (baik berupa kaidah baru atau mengubah kaidah lama) terhadap UUD 1945. Perubahan adalah amandemen model Amerika Serikat (Asshiddiqie dan Manan,2006;27). Dengan kata lain, amandement atau perubahan adalah dengan mempertahankan naskah asli, sedangkan perubahan kemudian dilekatkan pada naskah aslinya. Sehingga, naskah asli tetap terpelihara keasliannya, dengan demikian generasi seterusnya dapat mengetahui naskah pertama, undang-undang dasar tersebut. Ini merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap para pendahulu (the founding people) yang merupakan penyusun undang-undang dasar tersebut. Pemikiran ini juga didasari, bahwa ada beberapa bagian dari undang-undang dasar tersebut yang masih perlu bahkan relevan untuk dipertahankan, karena norma yang terkandung di dalamnya tidak usang/ketinggalan dari perkembangan kehidupan ketatanegaraan. Sehingga hanya beberapa bagian dari ketentuan konstitusi yang perlu untuk dirubah, diganti, untuk menyesuaikannya dengan perkembangan yang kemudian terjadi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara yang melakukan perubahan konstitusi tersebut. Menurut Bagir Manan (2000;12) pembaruan UUD adalah memperbarui UUD dengan cara menambah, merinci, dan menyusun ketentuan yang lebih tegas. Kata pembaruan di sini termasuk pula memperkukuh sendi-sendi yang telah menjadi konsensus nasional seperti dasar negara, bentuk negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan republik. Kalau disimak kembali pengertian yang diberikan oleh Bagir Manan, maka
I Gusti Ngurah Santika, SPd
56
pengertian yang diberikan tentang makna dari pembaruan hampir sama dengan amandemen undang-undang dasar. Karena kata menambah, merinci merupakan suatu bagian daripada proses amandemen terhadap undang-undang dasar. Sedangkan kata menyusun lebih dekat dengan kata membuat undang-undang dasar yang baru, sehingga dengan demikian, kata menyusun merupakan suatu kata yang lebih dekat dengan kata pembaruan yang berarti membuat undang-undang dasar yang baru atau mengganti undangundang dasar yang lama. Oleh karenanya, ketiga kata menambah, merinci dan menyusun sebenarnya memiliki arti kata yang mirip dengan kata merubah ketentuan undang-undang dasar yang lama, sehingga menjadi lain bunyinya seperti dahulu sebelum undang-undang tersebut dirubah. Berbeda dengan pengertian constitutional reform (pembaharuan konstitusi), yang dimaksud di sini adalah jika suatu konstitusi itu dirubah, maka yang kemudian akan berlaku adalah konstitusi yang baru sama sekali, yang jelasnya akan berbeda dengan konstitusi sebelumnya. Dengan demikian, hubungan antara konstitusi yang lama dengan konstitusi yang baru tidaklah memiliki kaitan, bahkan menurut Syahuri (2004;46) bahwa sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia, diantaranya adalah Belanda, Jerman, dan Perancis. Biasanya penggantian konstitusi yang dilakukan beberapa negara, dikarenakan bahwa konstitusi tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mampu mengakomodasi kehidupan ketatanegaraan bangsa tersebut. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa UUD yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat (Budiardjo,2008;181). Selain hal itu, yang juga menjadi penyebabnya adalah kadang-kadang adanya kebencian mendalam terhadap konstitusi yang lama serta didasari atas pengalaman sebelumnya, yang mana telah memberikan alasan pembenaran (justification) terhadap tindakan penguasa yang otoriter. Sehingga menyebabkan tidak ada pertimbangan sama sekali untuk kemudian mempertahankan naskah asli dari konstitusi tersebut, sehingga semua ketentuan yang ada di dalam konstitusi tersebut diganti dengan yang baru. Bahaya dari suatu penggantian konstitusi yaitu kemungkinan besar adalah dapat memicu krisis ketatanegaraan yang cukup berkepanjangan dalam suatu negara. Tidak lain disebabkan oleh nilai-nilai baru yang dianut oleh konstitusi tersebut ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan pada saat melakukan penggantian terhadap undang-undang dasar tersebut. Di lain pihak, bangsa tersebut belum tentu mampu untuk sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi yang baru tersebut dalam kehidupan ketatanegaraan (nominal). Pada umumnya, negara-negara demikian ini terhitung sebagai negara yang sistem politiknya belum mapan. Sistem demokrasi yang dibangun,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
57
masih bersifat jatuh bangun, dan masih bersifat trial and error. Negara-negara miskin dan sedang berkembang di Asia dan Afrika, banyak yang dapat dikatagorikan masih dalam kondisi demikian ini (Asshididdiqie,2009;178) Selain cara perubahan konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, ada lagi cara lain untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi. Kansil (2002;89) dalam hal ini membedakan pengertian perubahan konstitusi yang dilakukan secara disengaja dalam rumusan pasal tersebut verfassung anderung sedangkan perubahan yang tidak disengaja dibiarkan terjadi di dalam praktik disebut verfassung wandlung, menurutnya perubahan semacam ini terjadi melampaui hukum dasar tidak tertulis. Sedangkan menurut Kusnardi dan Sarigih (2008;150) yang menyatakan bahwa verfassung wandlung adalah perubahan undang-undang dasar dengan cara yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar tersebut, tetapi melalui cara istimewa seperti revolusi, coup detat, konvensi, dan sebagainya. Jadi, pada dasarnya dua ahli hukum di atas telah memberikan pengertian verfassung wandlung dengan makna yang sama. Sehingga verfassung wandlung berarti suatu perubahan yang sebelumnya terjadi dalam ketatanegaraan, namun dalam kenyataannya tidak mengikuti bunyi daripada konstitusi, yang seharusnya merupakan pegangan utama daripada kehidupan bernegara terutama dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi tersebut. Dengan demikian, praktik yang terjadi dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi merupakan suatu ketentuan yang kadang-kadang dapat saja berlawanan dengan bunyi dari konstitusi tertulis. Ataupun bisa saja dalam kenyataan praktik tersebut tidak tercantum ketentuan tentang tata cara perubahan terhadap konstitusi, padahal seharusnya ketentuan tersebut ada, sehingga kemudian dapat digunakan sebagai pedoman. Tentunya berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk diadakan suatu penyesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan tanpa melanggar konstitusi itu sendiri. Lain lagi menurut pendapat dari Budiardjo dalam Tim ICC UIN (2010;65) yang menyatakan ada empat macam prosedur dalam perubahan konstitusi baik dalam model renewel (pembaharuan) dan amandemen, yaitu: 1. Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan kourom untuk sidang membicarakan usul perubahan Undang-Undang Dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif atau menerimanya;
I Gusti Ngurah Santika, SPd
58
2. Referendum, pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usul perubahan undang-undang; 3. Negara-negara bagian dalam negara federal (misalnya Amerika Serikat, tiga perempat dari 50 negara-negara bagian harus menyetujui); dan 4. Perubahan yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Terkait dengan metode perubahan terhadap konstitusi atau undang-undang dasar, C.F Strong dalam Syahuri (2004;18) membedakan menjadi empat macam cara perubahan sebagai berikut. 1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu. 2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum. 3. Perubahan konstitusi dan ini berlaku di negara-negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. 4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Sementara, menurut K.C Wheare dalam Tutik (2008;117), cara mengubah konstitusi dapat dilakukan melalui empat cara: (1) some primary forces; (2) formal amandement; (3) judicial interpretation; (4) usages and costum.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
59
BAB II UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 A. Sejarah singkat perjalanan UUD 1945
Dengan diserangnya Pearl Harbour oleh Angkatan Udara Jepang, maka sejak tanggal 8 Desember 1941 terjadi peperangan antara Jepang dengan Amerika Serikat serta sekutusekutunya. Dalam waktu yang relatif singkat telah jatuh jajahan Inggris, Amerika Serikat dan Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942 Angkatan Perang Kerajaan Belanda yang berada di Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang (Soemantri,1979;14). Pesan radio terakhir dari kawasan yang dikuasai Belanda berbunyi: Kami mengundurkan diri. Selamat tinggal, sampai jumpa kelak disaat-saat yang lebih menyenangkan (Tahija,1997;38). Pernyataan Belanda tersebut tidak lain merupakan suatu hinaan terhadap bangsa Indonesia, yang sebelumnya telah dijajah selama 3 abad di bawah penindasannya dengan sistem kerja rodi yang pada dasarnya memaksakan penduduk untuk bekerja di bawah pemerintahan Belanda. Perginya Belanda dari bumi pertiwi ini tentunya membawa suatu harapan yang cukup besar, terutama untuk mencapai kemerdekaan yang memang sudah lama sekali didambakan oleh bangsa Indonesia. Karena tidak lain, setelah sekian lama berjuang untuk mengusirnya dengan berbagai macam cara, terutama lewat pemberontakan bersenjata, kecuali itu juga dengan cara-cara diplomasi dalam meja perundingan. Bahkan, Jepang yang telah berhasil menaklukan Belanda, kemudian menyatakan kepada bangsa Indonesia dengan penuh percaya diri serta meyakinkan, bahwa Jepang merupakan saudara tua daripada bangsa Indonesia, yang kedatangan hanya untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penindasan Belanda selama ini. Memang pada awal mula di masa pendudukan bala tentara Jepang, bangsa Indonesia pada waktu itu sangat mempercayai terhadap propaganda-propaganda yang telah dilancarkan oleh Jepang, terutama pada waktu kedatangannya 8 Maret 1942. Berbagai taktik yang dilakukan oleh Jepang semata-mata hanya untuk menarik hati bangsa Indonesia, seraya dengan tujuan untuk mendapatkan suatu dukungan yang luas daripada segenap komponen bangsa Indonesia dalam perang Asia Timur Raya. Berikut ini merupakan taktik yang pada dasarnya merupakan suatu tipu muslihat daripada bangsa
I Gusti Ngurah Santika, SPd
60
Jepang bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, dengan harapan kemudian bahwa bangsa Indonesia akan mendukung daripada tindakan Jepang dalam menghadapi kekuatan Sekutu pada saat berlangsungnya perang dunia kedua, yaitu. a. Jepang mempropagandakan bahwa kedatangannya untuk menolong bangsa-bangsa terjajah dan menyelenggarakan kemakmuran bersama dalam Asia Raya. b. Pemimpin Indonesia yang dibuang dan ditawan Belanda dibebaskan. c. Kedatangan Jepang disambut dengan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang dan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya (karena dikira akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan sesuai dengan ramalan Jayabaya). Tetapi ternyata rakyat Indonesia tertipu, karena kemudian segera keluar larangan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya (Rindjin,2009;42-43). Terkait dengan tujuan daripada kedatanganan bangsa Jepang ke Indonesia, seperti dinyatakan tersebut di atas yang kemudian disertai dengan berbagai janji, ternyata benarbenar mampu untuk sementara waktu meyakinkan bangsa Indonesia. Namun, semua janji tersebut sebenarnya hanyalah merupakan suatu tipu muslihat daripada bangsa Jepang itu sendiri untuk kemudian menutupi kedok buruknya yang merupakan tujuan sebenarnya. Berbagai tindakan Jepang yang begitu ramah pada awalnya merupakan hanya sebuah taktik semata, tidak lain hal ini dilakukannya untuk dapat merebut hati bangsa Indonesia, agar kemudian mendukung Jepang terutama dalam kaitannya dengan perang Asia Raya yang memang sedang berlangsung pada waktu itu. Namun, jika selanjutnya kita teliti kembali secara saksama terutama dengan fakta-fakta sejarah sebelumnya bahwa sebenarnya tujuan daripada kedatangan Jepang ke Indonesia adalah mengeksploitasi kekayaan daerah yang dijajah (Sukirno,2010;5). Bahkan, kedudukan Jepang yang hanya dalam kurun waktu 3 Tahun saja, namun dapat dikatakan merupakan suatu penindasan terkejam, yang selama ini mungkin pernah dialami bangsa Indonesia, yaitu selama dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Kekejaman Jepang terhadap rakyat Indonesia, selanjutnya dapat kita temukan kembali dalam sistem kerja paksa yang kemudian diterapkan oleh Jepang selama menjajah bangsa Indonesia, yaitu dengan nama romusa. Soekarno (1989;25) yang jauh-jauh hari sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia telah pula menyatakan dengan tegas tentang kejamnya suatu penjajahan. Dalam pidato pembelaannya di Landraad Bandung, Soekarno menyatakan bahwa tujuan penjajahan yang sesungguhnya ialah memeras keuntungan dari
I Gusti Ngurah Santika, SPd
61
suatu bangsa, yang lebih rendah tingkat kemajuannya. Bahkan, dengan lebih rendahnya tingkat kemajuan daripada suatu bangsa yang dijajah, baik dilihat dari sudut ekonomi, maupun pendidikan ternyata menyebabkan pula rendahnya kesadaran rakyat untuk kemudian memiliki kehendak bersama, yang bertujuan untuk membangun kehidupan sebagai suatu bangsa dalam arti politis, bukan sebagai rakyat jajahan. Namun, kemiskinan dan tertindasnya rakyat Indonesia sebenarnya merupakan awal mula daripada perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah, untuk berjuang sampai kemudian mendapatkan sebuah kemerdekaan yang abadi. Meskipun dalam kenyataannya pada waktu itu berbagai perlawanan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia selalu saja kandas atau mengalami suatu kegagalan, yang berarti tidak hanya mengorbankan harta benda namun tentunya juga jiwa dan raga. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, ialah karena kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah, kecuali itu adanya politik devide et impera(Slameto,2010;77) dari penjajah, di samping itu pula disebabkan oleh karena kalah modern dalam persenjataan antar penjajah dengan rakyat yang dijajahnya. Politik pecah belah dan menguasai, sebagaimana dimaksud oleh Slameto, merupakan senjata yang bisa dibilang sangat ampuh bagi setiap penjajah yang pernah bercokol di Indonesia. Dengan memanfaatkan keberaneka ragaman bangsa Indonesia, baik dilihat daripada berbagai pulau, maupun suku, etnis, agama, yang kemudian dihidupkannya kembali tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat, yang tentunya dalam hal ini akan semakin menjauhkan antara rakyat sendiri, untuk meraih sebuah persatuan guna melawan penjajah agar mampu meraih kemerdekaan. Selain itu, juga terlihat dengan jelas belum adanya suatu perlawanan secara menyeluruh (komperhensif) oleh rakyat terhadap para penjajah, tidak lain pada waktu itu dikarenakan oleh masih sangat tergantung daripada pemimpin, ditambah dengan diliputi oleh adanya semangat yang bersifat kedaerahan. Di samping itu, dikarenakan belum timbulnya kesadaran politik dari rakyat untuk membentuk satu bangsa Indonesia dalam arti politis, sebab terlihat masih memperjuangkan daerahnya sendiri, yang tentunya perjuangan tersebut hanya bertujuan untuk membentuk bangsa bersifat sosiologis antropologis. Tentunya dalam hal ini akan sangat menguntungkan penjajah, yang kemudian jika dilihat dari sudut kekuatan rakyat yang berjuang untuk melawannya. Namun, nampak terlihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia nantinya tidaklah dikatakan sia-sia, yang mana walaupun hanya dengan dibekali sebuah semangat dan senjata yang dapat dibilang seadanya namun, pada akhirnya ternyata mampu mewujudkan kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
62
Pada waktu Perang Pasifik, Jepang berkuasa atas sebagian besar daerah-daerah di Asia Timur dan Tenggara, termasuk Indonesia, oleh karena angkatan Perangnya (Noer,1983;10). Sementara itu, jika kita baca kembali dalam sejarah maka sejak akhir tahun 1943 perkembangannya menunjukan bahwa kekuasaan serta kedudukan Jepang di Asia mulai goncang dan terancam. Oleh karena kedudukan Jepang yang terlihat semakin terdesak oleh Sekutu, bukti nyata yang kemudian dapat menunjukan terdesaknya Jepang oleh Sekutu, ditandai dengan berbagai kekalahan Jepang dalam fron-fron peperangan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan Jepang mulai menunjukan simpatinya kepada orang-orang bangsa Indonesia, bahkan pada tanggal 7 September 1944 Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia nanti pada tanggal 24 Agustus 1945 (Soehino,1984;14). Pernyataan Jepang tentang ada suatu janji berupa pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dikemudian hari, juga dapat ditemui dan dibaca dalam Anshari (1986;15) yang menyatakan bahwa The Japanese Empire (hereby) announce the future independence of all Indonesian people. Memang sejarah menunjukan, bahwa di masa-masa yang genting, jika terjadi pergolakan-pergolakan internasional menimbulkan kegoncangan, maka pemerintah kolonial itu selalu memberikan hadiahhadiah(Subekti,1989;4). Janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari kepada Indonesia, tentu hanyalah merupakan sebuah taktik daripada Jepang, untuk kemudian menarik simpati dengan tujuan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari bangsa Indonesia guna melawan Sekutu, yang memang pada waktu itu posisinya kian lama makin mendesak kedudukan Jepang dalam peperangan, bahkan sudah sangat jelaslah terlihat kekalahan Jepang di depan mata. Karena itulah, samar-samar terlihat kebaikan Jepang kepada bangsa Indonesia dengan memberikan sebuah janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kelak di kemudian hari. Untuk mempersiapkan pelaksanaan janji Jepang seperti tersebut di atas, maka pada tanggal 29 April dibentuklah BPUPKI terdiri atas ketua Dr. K.R.T Rajdjiman Wedyodiningrat (Kansil dan Christine,2011;18) dan wakil ketua Itibangase Yosio serta R. P Soeroso dengan jumlah anggotanya sebanyak 60 orang yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 (Setneg,1995;xxv). BPUPKI merupakan badan buatan Jepang, sebagai realisasi daripada janji Jepang tentang pemberian kemerdekaan kepada Indonesia dikemudian hari. Perlu untuk di ketahui di sini bahwa pada awal mula dibentuknya badan ini oleh Jepang, ternyata bukanlah disertai dengan nama BPUPKI seperti yang kemudian dibaca dalam buku-buku seperti sekarang ini, melainkan BPUPK nama yang sebenarnya diberikan oleh Jepang terhadap badan ini. Namun, tidaklah mengurangi makna yang sama dengan kedua
I Gusti Ngurah Santika, SPd
63
istilah tersebut di atas, tidak lain dikarenakan sudah menjadi kelaziman dalam dunia akademis yang selama ini memberikan nama Indonesia di belakangnya, maka untuk sekarang sudah merupakan suatu kesepakatan bersama, dapatlah dikatakan demikian. Dalam sejarahnya badan penyelidik ini mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli1945 (Syam,1987;14). Badan ini memiliki tugas yaitu secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat bagi suatu negara merdeka (Darmodiharjo,1984;47). Dalam sidang BPUPKI yang pertama, ternyata ada tokoh-tokoh bangsa berpidato yaitu Muh Yamin (29 Mei 1945), Sopomo (31 Mei 1945), dan Soekarno (1 Juni 1945), yang semata-mata hanya untuk menanggapi pertanyaan dari ketua BPUPKI Radjiman Widyodiningrat tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dari berbagai pidato yang kemudian disampaikan tersebut, mungkin pidato yang paling menarik adalah apa yang telah disampikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Perlu diketahui, bahwa nantinya hasil dari pekerjaan BPUPKI akan dibahas kembali dalam suatu badan yang bertugas untuk selanjutnya menetapkan kemerdekaan Indonesia secara final. Dengan demikian, hasil pekerjaan dari BPUPKI tersebut dimaksudkan tidaklah bersifat mengikat daripada panitia yang selanjutnya akan menggantikannya kelak dikemudian hari. Itulah maksud daripada Jepang untuk membentuk sebuah badan yang bernama BPUPKI, sehingga dari hal tersebut dapatlah diketahui bahwa kehendak Jepang untuk memberikan suatu kemerdekaan yang berupa janji tersebut kepada bangsa Indonesia, tidaklah sepenuhnya didasari oleh adanya kehendak yang sifatnya tulus untuk benar-benar memberikan sebuah kemerdekaan. Dikarenakan dapat dipastikan bahwa panitia yang selanjutnya dibentuk tersebut, tentunya akan kembali mengadakan sidang mulai dari awal untuk mempersiapkan kembali kemerdekaan Indonesia, yang mana dikarenakan tidak mengikatnya hasil-hasil kerja daripada badan yang bernama BPUPKI. Dengan demikian, dapatlah dipastikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan kunjung tercapai, karena hanya berdebat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selain dibentuknya BPUPKI sebagai badan yang secara legal bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, dalam kenyataannya juga dibentuk sebuah Panitia Kecil yang selanjutnya diketuai oleh Soekarno dengan 7 orang anggota, yang memiliki tugas untuk menampung dan memeriksa semua usul anggota mengenai usaha persiapan kemerdekaan. Panitia Kecil tersebut dalam menjalankan tugasnya mengadakan sidang pada tanggal 22 Juni 1945 dengan anggota-anggota badan penyelidik dalam sidang tersebut yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
64
dihadiri sekitar 38 orang, yang memang berada di Jakarta. Pertemuan antara 38 orang anggota itu bertempat di gedung kantor besar Jawa Hooko Kai. Dari pertemuan itulah mereka kemudian membentuk panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang anggota dan popular disebut dengan nama Panitia Sembilan. Dalam sidang tersebut dicapai suatu kesepakatan tentang rancangan UUD yang kemudian disebut dengan nama Piagam Djakarta. Menurut keterangan yang kemudian diperoleh dari Mahmud MD (2009;19) dalam bukunya berjudul Konstitusi dan Hukum, menyatakan bahwa berkaitan dengan kedudukan panitia 8 (Delapan) dibandingkan dengan panitia Sembilan (9), dengan tegas ia menyatakan bahwa Panitia 8 inilah sebenarnya merupakan panitia yang resmi bentukan BPUPKI, sedangkan panitia 9 merupakan panitia tidak resmi yang dibentuk sendiri oleh Soekarno ketika sidang VIII 38 orang anggota Cou Sangi in 18-21 Juni 1945 di Jakarta. Hal mana disebabkan oleh keadaan yang pada waktu itu sangat mendesak, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan prosedural formal belaka, itulah pernyataan Soekarno di depan ketua BPUPKI dalam laporannya. Dalam cerita sejarahnya, kekalahan Jepang berturut-turut di berbagai pron peperangan dalam melawan Sekutu, yang selanjutnya disusul dengan suatu peristiwa dramatis, yaitu terutama pada saat Amerika Serikat melakukan pengeboman terhadap kota Hirosima pada tanggal 6 Agustus 1945, telah menyebabkan kedudukan Jepang semakin tersudut. Kemudian pada tanggal 7 Desember 1945 tentara Jepang mengumumkan akan membentuk sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan (Dukuritu Zyunbi Iinkai) dengan tujuan untuk memeriksa hasil-hasil kerja dari BPUPKI. Yang nantinya setelah merdeka badan PPKI tersebut merupakan badan yang mewakili seluruh golongan di Indonesia. Setelah badan ini disempurnakan dan ditambah dengan wakil-wakil daerah dan golongan sehingga lebih memenuhi syarat sebagai suatu Badan Perwakilan Rakyat yang bersifat nasional (PPKI gaya baru) maka segera ditugaskan untuk menyusun alat-alat perlengkapan negara (IKIP Malang,1979;48). Sebelum dibentuknya PPKI yang selanjutnya akan menggantikan BPUPKI, beberapa tokoh bangsa Indonesia yaitu Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat pergi ke Saigon dengan tujuan untuk memenuhi panggilan daripada Jenderal Terauchi. Dalam pertemuannya tersebut ditetapkan bahwa Indonesia akan segera membentuk sebuah badan PPKI, sedangkan terkait dengan waktu dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia adalah tergantung dari usaha bangsa Indonesia sendiri.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
65
Kaelan (2008;44) menyatakan bahwa sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran Ir. Soekarno mengumumkan di muka orang banyak bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin), dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sementara itu, pada tanggal 9 Agustus 1945 Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Sekutu sampai akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Bahkan menurut Agung (1995) bahwa pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan dengan demikian berakhirlah Perang dunia II. Dengan demikian, lenyaplah janji kemerdekaan dari Jenderal Terauchi. Dengan penandatanganan penyerahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu di atas kapal Amerika Serikat missouri lenyap pulalah cita-cita Jepang untuk membentuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah pimpinannya (Tutik,2008;127). Dengan kata lain, Jepang yang kalah perang pada waktu itu, harus tunduk pada perintah Sekutu, yang pada dasarnya merupakan pemenang dalam perang dunia ke II. Sehingga secara otomatis Jepang tidak memiliki kewenangan apapun terhadap semua daerah jajahannya. Tidak lain hal ini dikarenakan adanya suatu perjanjian yang isinya menyatakan berupa perintah dari Sekutu kepada Jepang, agar tetap mempertahankan status quo terhadap daerah-daerah jajahannya, sehingga tidak mungkin dapat melakukan tindakan apapun terhadap semua daerah jajahannya, kecuali atas perintah-perintah yang selanjutnya diberikan oleh Sekutu. Oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali bahwa janji Jepang yang sebelumnya akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia tidak mungkin dapat dilaksanakan lagi dan di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan (Widjaja,1987;10). Terjadinya kekosongan kekuasaan (vacuum of power) merupakan suatu kesempatan bagi bangsa Indonesia yang sebenarnya tidak boleh disia-siakan untuk selanjutnya menyatakan sendiri kemerdekaannya. Sehingga dengan demikian, kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari bangsa lain, melainkan usaha yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Perlu diketahui pada waktu itu, bahwa terkait dengan adanya kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu, ternyata imformasinya belumlah begitu banyak yang mengeketahui termasuk oleh pemimpin-pemimpin perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan, akibat adanya kesimpangsiuran berita tentang kekalahan Jepang, pada akhirnya telah menyebabkan ketegangan antara Soekarno-Hatta dengan para pemuda, yang kemudian berakibat Soekarno dan Hatta diamankan oleh para pemuda ke Rengasdengklok. Ini dilakukan tidak lain disebabkan adanya perbedaan pendapat terkait waktu pelaksanaan kemerdekaan, yang berbeda kehendak antara golongan tua dengan golongan muda tersebut. Dalam masalah ini golongan muda ingin cepat-cepat untuk dilaksanakannya suatu
I Gusti Ngurah Santika, SPd
66
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dilain pihak golongan tua menyatakan belum tiba saatnya untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, dikarenakan belum adanya kepastian tentang berita kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Namun, setelah memperoleh kepastian bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, maka Dwitunggal Soekarno Hatta setuju untuk kemudian dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan, akan tetapi tempat dilaksanakan kemerdekaan Indonesia adalah di Jakarta. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Terkait dengan kemerdekaan Indonesia yang telah diperoleh, Kansil (1985;20) berpendapat bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sampailah perjuangan rakyat Indonesia mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia ke Jembatan Emas Kemerdekaan. Salah satu pendapat yang menurut penulis sangatlah menarik terutama dari pernyataan Kartohadiprodjo dalam Sutrisno (2006;70) terkait dengan adanya pernyataan kemerdekaan Indonesia yakni berkenaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menurut sudut ketatanegaraan merupakan suatu pembrontakan atau revolusi. Tidak lain dikarenakan Indonesia (Hindia Belanda) dulu merupakan bagian daripada Belanda, pernyataan tersebut setidaknya adalah menurut Konstitusi Belanda pada waktu itu. Namun, perjuangan bangsa Indonesia sebagai sebuah revolusi tidak dimulai dalam waktu yang singkat, namun sudah melalui perjalanan yang sangat panjang dengan mengorbankan semangat serta jiwa dan raga demi kepentingan bangsa. Revolusi nasional yang merupakan lanjutan dari rentetan konflik bersenjata sejak Belanda menanamkan kekuasaannya di Indonesia, meletus pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam bentuk Proklamasi Kemerdekaan (Djumhur dan Danasaputra,1976;199). Apakah yang sebenarnya dapat membenarkan tindakan bangsa Indonesia untuk kemudian melakukan revolusi terhadap penjajahan Belanda, sehingga dapat mencapai kemerdekaan dengan adanya pernyataan suatu proklamasi kemerdekaan? Dengan demikian, keberhasilan bangsa Indonesia dalam melakukan suatu revolusi untuk melawan penjajahan merupakan tindakan yang dapat dikatakan sah dan selanjutnya dibuktikan kemudian dengan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut selanjutnya diperkuat lagi oleh Suny dalam Joeniarto (1982;41) yang menyatakan bahwa dari sudut pandangan hukum, suatu revolusi yang jaya dengan sendirinya merupakan suatu kenyataan yang menciptakan hukum. Suatu revolusi yang berhasil jelas menunjukan bahwa pemerintah (atau negara) yang digulingkan itu tidak mempunyai cukup kekuasaan untuk melaksanakan undangundangnya (Rodee,2011;31). Dengan demikian, mungkin dulunya menurut hukum kolonial tindakan bangsa Indonesia merupakan suatu perbuatan dalam bentuk pemberontakan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
67
(subversi), tentunya tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat menentang pemerintahan sah. Oleh karena itu, tentu saja jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku pada waktu itu (hukum positif, ius costitutum). Namun, kemudian jika lihat kembali dari sudut pandang keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengkosolidasikan kekuasaan, yang merupakan hasil dari kemerdekaannya, lebih lanjut diikuti dengan kemampuan untuk mempertahankan tertib hukumnya yang baru dibentuk, maka tidak lain bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa sah yang sebenarnya terlahir dari rahim revolusi. Terkait dengan revolusi atau kudeta, jika ditinjau kemudian dari sudut hukum internasional, Kelsen (2011;314) kemudian berpendapat bahwa. Revolusi atau kudeta yang berhasil adalah yang tidak menghancurkan identitas tatanan hukum yang dirubahnya. Tatanan hukum yang ditegakan oleh revolusi atau kudeta harus dipandang sebagai modifikasi dari tatanan hukum lama, bukan sebagai tatanan hukum baru, jika tatanan hukum ini berlaku untuk teritorial yang sama. Pemerintahan yang berkuasa melalui suatu revolusi atau kudeta, menurut hukum internasional, adalah pemerintahan yang sah dari negara tersebut, yang identitasnya tidak dipengaruhi oleh peristiwa ini. Karena itu, menurut hukum internasional, revolusi atau kudeta yang berhasil harus ditafsirkan sebagai prosedur perubahan tatanan hukum nasional. Kedua peristiwa ini, ditinjau dari sudut hukum internasional, merupakan fakta pembentukan hukum. Demikian pula, e injuria jus oritur, dan lagilagi efektivitaslah yang diterapkan. Tindakan revolusi yang sebelumnya diambil oleh bangsa Indonesia, tidak lain merupakan tujuan yang memang sudah lama diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia, yang selama ini dalam sejarahnya telah mengalami berbagai bentuk penindasan oleh penjajahan, yang tidak kurang dari tiga setengah abad di bawah penjajahan Belanda dan tiga setengah tahun di bawah penjajahan Jepang. Sedangkan tujuan revolusi Indonesia itu sendiri menurut Soepomo (2003;1) merupakan suatu revolusi melawan Barat yang tidak hanya semata-mata suatu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan politik. Namun, juga merupakan suatu revolusi sosial dan ekonomi, yang ditimbulkan oleh suatu bangsa yang telah bertekad sebulat-bulatnya, untuk menempatkan nasib Indonesia dalam tangannya sendiri. Hampir sama dengan pendapat dari Soepomo, Andasasmita (1983;58) juga menyatakan bahwa kemerdekaan politik di Indonesia, setelah terjadinya revolusi melawan penjajahan Barat (Belanda), selain bertujuan untuk mencapai kemerdekaan politik, juga merupakan suatu revolusi sosial dan ekonomi dari rakyat Indonesia yang bertekad menempatkan nasibnya dalam tangannya sendiri, oleh karena kemerdekaan politik hanyalah suatu jembatan dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
68
membangun kembali masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kemerdekaan politik hanya merupakan suatu jalan untuk kemudian mencapai kemerdekaan lainnya, seperti ekonomi dan sosial. Terkait dengan pendapat tersebut di atas, maka lebih lanjut Seomantri (1992;16) menyatakan bahwa dari sejarah umat manusia kita mengetahui bahwa dianutnya faham kemerdekaan mempunyai pengaruh pula dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Soekarno (1989;71) jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia dicapai telah menyatakan dengan tegas bahwa mencapai kekuasaan politik bagi rakyat jajahan adalah berarti mencapai pemerintahan nasional, mencapai kemerdekaan nasional, mencapai hak untuk mengadakan undang-undang sendiri, mengadakan aturan-aturan sendiri, mengadakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian, hanya dengan kemerdekaanlah kita dapat bebas untuk selanjutnya menentukan nasib kita sendiri, serta bebas untuk berpolitik yang pada akhirnya mampu mencapai kesejahteraan rakyat. Revolusi kemerdekaan 17 Agustus 1945, merupakan revolusi yang membutuhkan waktu yang lama, namun hasil-hasil dari revolusi tersebut sangatlah mendasar. Hal ini dikarenakan Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan contoh suatu revolusi yang tepat momentum nya. Pada waktu itu, perasaan tidak puas di kalangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya dan ada pemimpin-pemimpin yang mampu menampung keinginan-keinginan tersebut, sekaligus merumuskan tujuannya (Soekanto,2009;271). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa revolusi Indonesia bertujuan untuk mencapai kemerdekaan, seperti sebagaimana dimaksudkan di atas, bukanlah sesuatu hal yang tidak direncanakan, namun sudah direncanakan secara matang melalui perjuangan sejak dahulu kala, di mana pada saat dimulainya penjajah menancapkan kuku imperialismenya di Indonesia. Dimulai dari Zaman Perintis di mana pada waktu dibentuk berbagai organisasi yang kemudian melopori perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui pergerakan nasionalnya, yaitu Budi Utomo (20 Mei 1908) kemudian perjuangan berlanjut dengan adanya Ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) yang kemudian lebih dikenal dengan nama Zaman Penegas dan barulah kemudian dengan datangnya Zaman Pendobrak (17 Agustus 1945) yang ditandai, adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (lihat Winarno,2009;147). Bahwa, hanya dengan kemerdekaan politik berupa suatu proklamasi kita dapat membentuk tertib hukum, yang merupakan sumber hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang merdeka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaga Administrasi Negara,tt;1). Dalam hal ini Joeniarto (1996;10) menyatakan bahwa
I Gusti Ngurah Santika, SPd
69
proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah merupakan perwujudan formal daripada salah satu gerakan revolusi bangsa Indonesia, untuk menyatakan baik kepada diri kita sendiri, maupun kepada dunia luar (dunia internasional), bahwa bangsa Indonesia mulai pada saat itu telah mengambil sikap untuk menentukan bangsa dan nasib tanah air. Kemerdekaan adalah syarat yang amat penting baginya untuk bisa melawan dan memberhentikan imperialisme itu dengan seleluasa-leluasanya. Kemerdekaan adalah pula syarat yang amat penting bagi pembaikan kembali segala susunan pergaulan hidup suatu negeri bekas jajahan, suatu syarat yang amat penting bagi rekonstruksi nasionalnya. Menurut Santoso (2010;37) proklamasi kemerdekaan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut yuridis dan politis. Dari segi yuridis, proklamasi kemerdekaan merupakan saat tidak berlakunya hukum kolonial dan saat mulai berlakunya hukum nasional, sedangkan dari segi politis, proklamasi kemerdekaan mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Semakin jelaslah bahwa, hanya dengan menyatakan suatu Proklamasi Kemerdekaan oleh bangsa Indonesia adalah suatu pertanda untuk kemudian memutuskan ikatan sejarah dengan bangsa penjajah, sekaligus mengukuhkan hukum nasional dan merupakan bentuk penolakan secara tegas terhadap hukum kolonial. Yang kemudian kemerdekaan itu sendiri merupakan cerminan sebagai bangsa yang berdaulat, baik secara de facto maupun de yure yang sebelumnya memang telah diperjuangkan oleh rakyat. Dengan demikian, dapatlah kemudian dikatakan bahwa kemerdekaan ini berarti perjuangan seluruh rakyat. Oleh sebab itu, Republik Indonesia ini milik seluruh rakyat (Lubis dkk,1981;18) Setelah adanya Proklamasi Kemerdekaan sebelumnya dinyatakan dengan tegas, yang kemudian disertai dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk semangat perjuangan bangsa, perlulah diingat kembali bahwa kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh wakil Bangsa Indonesia SoekarnoHatta di Jakarta... (Susanto,1985;15). Yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno mengadakan sidang(Santoso,2010;37), sedangkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai P. Y. M. (baca: Paduka Yang Mulia, pen) sendiri sebelum dipilih menjadi Presiden dan dengan P.Y.M. Drs Mohammad Hatta sebelum menjadi Wakil Presiden sebagai wakil ketuanya,(Notosusanto,1984). Selain mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi oleh PPKI, peristiwa lainnya yang pada waktu itu memiliki kaitan lainnya terutama dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu dalam sidangnya yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu dengan ditetapkan Undang-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
70
Undang Dasar (Notonagoro,1974;42). Undang-Undang Dasar yang telah disahkan oleh Panitia Persiapan tanggal 18 Agustus 1945 tersebut di atas, bahan-bahannya telah dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dukuritsu Junbi Cosakai), disingkat : Badan Penyelidik(Panyarikan,1981;198). Walaupun pada saat itu PPKI menetapkan UUD 1945 hanya dalam waktu 2 jam (Winarno,2009;72), namun dengan semangat kenegarawanan yang dimiliki oleh para pendiri bangsa ini, ternyata mampu untuk memperpendek jarak perbedaan yang ada, sampai akhirnya kemudian berhasil mengesahkan hukum dasar yang pertama. Walaupun pada saat penetapan UUD 1945, sempat diliputi oleh suasana yang sangat menegangkan. Namun akhirnya berhasil, tidak lain dikarenakan berkat perjuangan seluruh bangsa Indonesia UUD 1945 tetap berlaku di seluruh tanah air (Kansil,1985;1). Dengan demikian, mulai tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini setidaknya bangsa Indonesia ternyata mengenal paling tidak lima konstitusi yang pernah berlaku, yaitu selain hukum dasar hasil karya BPUPKI. Berikut ini merupakan undang-undang dasar dari beberapa periode, yang pernah berlaku di Indonesia dan gerak pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai perwujudan dari sistem konstitusi yang dimiliki oleh bangsa ini, yaitu sebagai berikut. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 (Masa Revolusi). Tidak lama setelah berlakunya UUD 1945 setelah ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 muncul gerakan untuk tidak memberlakukan UUD 1945, yang terutama dipelopori oleh Sjahrir, BM. Diah, dan lain-lain pemuda. Hal tersebut terjadi menurut Soebagio (1977;39) dikarenakan bahwa ketentuan pasal IV Aturan Peralihan UUD itu ternyata dalam dunia internasional telah mengundang kesan bahwa negara yang baru berdiri dengan nama republik Indonesia itu menganut pemerintahan diktaktor. Hal mana dapat dimengerti, dikarenakan bahwa besarnya kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 pada waktu itu hanya kepada satu orang, yaitu presiden yang kemudian menyebabkan seolah-olah menjadikan UUD 1945 itu sendiri sebagai sebuah konstitusi bersifat tidak demokratis. Alasan itulah yang dijadikan tumpangan oleh Belanda untuk menghancurkan Indonesia, dengan mempropagandakan kepada dunia internasional, bahwa negara Indonesia yang baru berdiri adalah buatan Jepang yang bersifat fasis. Diberikannya kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden oleh UUD 1945, tidak lain dikarenakan pada saat pemberlakuan UUD 1945, diliputi oleh sutuasi dan kondisi yang sangat mendesak. Dimana pada saat itu memang sedang berkecamuk perang pasifik, bahkan adanya keinginan pihak Belanda untuk menjajah Indonesia kembali. Dalam keadaan yang demikian, tentunya tidak mungkin bagi bangsa Indonesia untuk dapat membentuk lembaga-lembaga negara, seraya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
71
membagi-bagikan kekuasaan seperti sebagaimana diinginkan oleh UUD 1945 itu sendiri. Dalam masa berlakunya UUD 1945 yang masih murni, yakni sejak 18 Agustus 1945 sampai 14 November, roda pemerintahan dalam negara Republik Indonesia belum bekerja sempurna. Meskipun UUD 1945 telah memberikan kekuasaan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur berbagai peraturan perundangundangan negara, namun oleh suasana kenegaraan yang masih diliputi oleh masalahmasalah perlawanan terhadap pihak penjajahan yang bermaksud kembali meneruskan penjajahannya, maka lembaga-lembaga dan pranata-pranata kenegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia masih belum berkembang sebagaimana mestinya (Attamimi,1990;247). Oleh karena itu, sebagai jalan keluarnya yang kemudian diambil oleh PPKI sebagai lembaga berwenang untuk menetapkan UUD 1945, maka pada waktu itu dibuatlah rumusan Pasal IV Aturan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional (kursif penulis). Dengan adanya ketentuan tersebut, disertai dengan harapan bahwa Presiden akan dapat lebih efektif dalam mengambil tindakan, terutama apabila Presiden membutuhkan keputusan yang cepat, guna menanggapi situasi dan kondisi pada waktu itu. Namun, jika disimak kembali dengan cermat, bahwa dengan adanya ketentuan dari Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, menyebabkan tidak adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga negara sebagaimana dimaksud UUD 1945. Namun, perlu diingat bahwa adanya ketentuan tersebut pastinya hanyalah bersifat untuk sementara waktu saja. Ketentuan tersebut akan menjadi tidak berlaku, jika saja natinya sudah dibentuknya lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, hal mana adalah terlihat jelas dari maksud ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan tersebut. Namun, terkait dengan situasi adan kondisi pada saat itu, pembentukan lembaga baru seperti MPR, DPR, dan DPA memang tidak mungkin dapat dilakukan, maka jalan keluarnya untuk sementara waktu, yaitu Presidenlah yang kemudian akan menjalankan kekuasaan lembaga-lembaga negara tersebut, seperti apa yang tercantum secara jelas dalam ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Sehingga secara otomatis, dengan adanya ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, semua kekuasaan lembaga-lembaga negara yang waktu itu memang belum sempat dibentuk, sebagaimana dimaksud tulisan di atas, akan dilaksanakan oleh Presiden sepenuhnya. Bahkan, pada dasarnya UUD 1945 sendiri merupakan undang-undang dasar yang masih
I Gusti Ngurah Santika, SPd
72
bersifat sementara (intrim), karena undang-undang dasar tersebut dibuat dalam keadaan yang sangat mendesak. Sehingga, Soekarno menamakan UUD 1945 sebagai konstitusi revolusi, yang dalam hal ini juga ditegaskannya kembali dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada waktu pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, bahwa UUD 1945 merupakan suatu undang-undang dasar yang bersifat sementara. Yang nantinya jikalau kehidupan kenegaraan sudah lebih baik, akan dibentuk kembali undangundang dasar baru, yang selanjutnya akan menggantikan undang-undang dasar tersebut. Namun, setelah disahkannya UUD 1945 oleh PPKI, khususnya yang berkaitan dengan adanya ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan, kemudian seolah-olah telah menyebabkan kekuasaan Presiden cenderung menjadi absolute. Setidaknya demikianlah pandangan negara-negara Barat terhadap sistem pemerintahan yang dianut pada waktu itu oleh bangsa Indonesia. Banyak kecaman yang kemudian dilontarkan oleh para pemuda, terkait dengan adanya ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, karena dengan adanya ketentuan tersebut, berarti telah menempatkan kekuasaan Presiden yang begitu besar, yang mana tentunya akan berpotensi menjadikan Presiden sebagai penguasa dengan sifatnya yang otoriter. Untuk menanggapi respon dari kaum muda pada waktu itu, maka pada tanggal 16 Oktober 1945, atas pertimbangannya sendiri Moh. Hatta dengan mengatas namakan Presiden, kemudian mengeluarkan Maklumat No. X yang selanjutnya ditanda tangani sendiri olehnya. Maklumat ini ternyata telah mengubah bunyi dari ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yang memang pada awalnya hanya menempatkan kedudukan KNIP sebagai pembantu Presiden. Kemudian dengan keluarnya maklumat tersebut, telah menyebabkan berubahnya kedudukan dari KNIP yang sebelumnya ditentukan sebagai pembantu Presiden, kemudian menjadi sebuah badan legislatif yang bersifat otonom dan memiliki kedudukan sejajar dengan Presiden. Dengan adanya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, kemudian terjadilah perubahan dalam praktek ketatanegaraan. Namun, bukan berarti terjadi perubahan terhadap naskah UUD 1945, dikarenakan UUD 1945 itu sendiri tetap utuh seperti semula terutama berkaitan dengan ketentuan dari Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal IV Aturan Peralihan yang sebelumnya menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan yang sangat besar, yaitu dikarenakan selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, ternyata presiden juga ditentukan memegang kekuasaan lembaga negara lain, seperti MPR,DPR dan DPA. Namun, seketika itu dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 telah mengakibatkan kekuasaan Presiden terutama dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
73
bidang legislatif berkurang. Menurut penulis, dapatlah dikatakan bahwa Maklumat Wakil Presiden No X Tahun 1945 berkaitan dengan materinya tentu memiliki kedudukan sejajar dengan segala ketentuan yang ada pada UUD 1945. Tidak lain hal ini dikarenakan, dengan adanya Maklumat tersebut ketentuan dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 menjadi tidak berlaku. Idealnya sebuah peraturan hanya dapat dihapuskan oleh peraturan yang kedudukan lebih tinggi ataupun aturan yang kedudukan sederajat dengan yang dirubahnya. Namun, jika Maklumat Wakil Presiden No. X tersebut, kita dikatakan kedudukannya berada pada posisi lebih rendah dari UUD 1945, khususnya dengan ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan, pastinya ketentuan dari Maklumat tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mungkinlah kemudian dapat merubah praktek guna menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan pada saat itu juga. Terkait dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945, apakah yang telah menyebabkan Maklumat tersebut kemudian dinamakan dengan Maklumat Wakil Presiden, kenapa bukan dinamakan dengan Maklumat Presiden, padahal pada waktu itu Hatta yang menandatangani Maklumat tersebut atas nama Presiden. Menurut Radjab (2005;193) terkait penyebab Hatta yang menandatangani maklumat tersebut atas nama Presiden dikarenakan, hal ini dilakukan untuk mewakili Pemerintah sebab pada saat itu Presiden Soekarno tidak dapat hadir karena kepergiannya ke luar kota sehingga secara yuridis sebetulnya maklumat tersebut harus dinamakan maklumat Presiden. Terkait dengan keabsahan Maklumat tersebut, Mahmud MD (2010;26) dengan tegas menyatakan bahwa ihwal konstitusional atau dasar konstitusional dikeluarkannya Maklumat Nomor. X Tahun 1945 sebenarnya tak perlu lagi dipersoalkan sebab faktanya Maklumat tersebut langsung dan diikuti dalam praktik ketatanegaraan meskipun tanpa secara resmi disertai pencabutan atas UUD 1945. Maka dapat kemudian dikatakan bahwa keberlakuan Maklumat tersebut tidak hanya selanjutnya diterima secara politis, namun juga diterima secara sosiologis oleh rakyat Indonesia melalui praktek. Walaupun dalam kenyataannya jika dilihat dari sudut yuridis, adanya ketentuan Maklumat Wakil Presiden tersebut terlihat berlawanan dengan ketentuan UUD 1945, khususnya dengan ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan. Namun, tidaklah kemudian mengurangi legitimasi yang telah dimiliki oleh Maklumat Wakil Presiden tersebut, karena pada dasarnya semua orang memang mendukungnya, yang selanjutnya ditandai dengan dilaksanakannya ketentuan dalam Maklumat tersebut, yang berarti tidak mengikuti bunyi dari ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Bahkan dapat dikatakan bahwa dengan adanya ketentuan Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945, merupakan awal mula daripada tindakan pemimpin bangsa untuk selanjutnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
74
meletakan suatu prinsip-prinsip/sendi-sendi daripada konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai sebuah negara demokrasi yang demokratis. Dengan demikian, KNIP sendiri merupakan awal dari kelahiran lembaga legislatif Indonesia, sehingga unsur demokrasi, dalam rangka pembentukan undang-undang nampak secara perlahan-lahan namun pasti (Soehino,2010;59). Bahkan terkait dengan hal tersebut di atas, Dahl (2001;65) menyatakan bahwa pemerintah kolonial secara tidak sengaja telah membantu pada terbentuknya kepercayaan dan lembaga-lembaga demokrasi. Bahkan, kekuasaan legislatif yang kemudian diterima oleh KNIP itu sendiri, merupakan akibat daripada tekanan secara tidak langsung dari penjajah, namun perlu diakui merupakan sesuatu yang memang perlu untuk dilakukan. Maklumat tersebut merupakan pemotong potensi untuk menjadikan Presiden sebagai seorang penguasa diktaktor, dengan menempatkan lembaga KNIP sebagai sebuah lembaga perwakilan, yang nantinya mampu mengimbangi kekuasaan Presiden dalam bidang pembentukan undang-undang. Dengan berlakunya Maklumat No.X ini, maka kedudukan KNIP bukan lagi badan pembantu semata-mata, tetapi menjadi badan yang berwenang penuh yakni bersama-sama dengan presiden melaksanakan wewenang perundangundangan (menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1), 20, 21, dan 22 ayat (2) UUD 1945) dan malahan ikut pula menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara (sebagian tugas MPR yang tersebut dalam ketentuan Pasal 3 UUD 1945) (Kansil,1985;128). Jadi, yang paling penting dari keluarnya Maklumat Wakil Presiden No X Tahun 1945, adalah bertujuan untuk kemudian menciptakan sebuah pemerintahan yang pada dasarnya mengandung gagasan konstitusionlisme. Akan tetapi, apabila dikaji Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang telah dikemukakan, jelas bukanlah suatu pemberitahuan atau pengumuman. Bahkan, seperti telah diuraikan penulis di atas bahwa maklumat tersebut berisi materi muatan undang-undang dasar. Maklumat tersebut ternyata bukan satu-satunya peraturan yang mempunyai kedudukan dalam bidang hukum tata negara (Soemantri,1985). Dikarenakan nantinya dalam sejarah perjalanan revolusi bangsa Indonesia dalam usahanya untuk mempertahankan kemerdekaan, akan dikeluarkan kembali berbagai bentuk peraturan lainnya, yang dalam kenyataannya juga memiliki kedudukan penting secara konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Ghaffur (2011;80) terkait dengan keluarnya Maklumat No. X menyatakan bahwa masa bulan madu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Soekarno sedikit berkurang dengan dikeluarkannya Maklumat No. X oleh Wakil Presiden Moh. Hatta atas Usul dari Komite Nasional Pusat yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 1945.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
75
Ada beberapa pendapat para pakar Hukum Tata Negara dan politik mengenai Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945, antara lain yang menyatakan bahwa Maklumat Wakil Presiden tersebut adalah jalan keluar yang terbaik pada saat itu agar perjuangan Indonesia melalui jalur politik (perundingan dengan negara-negara lain terutama negara-negara Barat) di samping perjuangan senjata melawan agresi Belanda dapat berjalan mulus, dan pendapat lain yang mengatakan bahwa pembentukan kabinet parlementer dalam UUD 1945 berdasarkan Maklumat Wakil Presiden tersebut adalah perjuangan terhadap UUD 1945 (Sarigih dalam Hutabarat dkk,1996;37). Nampaknya, kelirulah menyatakan bahwa Maklumat Wakil Presiden berfungsi sebagai dasar daripada pembentukan sistem pemerintahan parlementer, dikarenakan pada dasarnya Maklumat Wakil Presiden tersebut hanyalah mengubah kedudukan daripada KNIP. Yang semula kedudukan KNIP hanya sebagai pembantu Presiden, sebagaimana dimaksudkan bunyi dari ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian dengan keluarnya Maklumat tersebut kedudukan KNIP berubah menjadi sebuah badan yang memiliki kedudukan sejajar dengan Presiden terutama dalam bidang pembentukan undang-undang. Kedudukan sejajar yang dimaksud adalah seperti apa yang sebelumnya telah ditentukan dalam pasal-pasal UUD 1945. Maklumat Wakil Presiden bukannya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer sebagaimana pernyataan Sarigih seperti yang dikutip oleh Hutabarat. Lebih lanjut terkait dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945, nampaknya masih banyak orang yang belum mengetahui dan memahaminya, maka untuk memperjelas maksud dari Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 oleh Moh. Hatta di atas, maka dalam hal ini Mahmud MD (2009;119) menyatakan bahwa istilah nomor X bukanlah nomor sepuluh (number ten) dalam angka Romawi melainkan X dalam arti tidak dikenal pasti karena bukan merupakan urutan dari peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Ketika Maklumat itu dibuat di kantor KNIP, Menteri Sekretaris Negara Ag. Pringgodigdo tidak ingat nomor urut UU yang telah ada sehingga ketika diminta nomor oleh KNIP dan Bung Hatta dia mengusulkan Nomor X saja. Selain adanya ketentuan seperti Maklumat Wakil Presiden seperti di atas, tidak berselang dalam waktu yang cukup lama, kemudian menyusul pula berbagai bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa untuk menyikapi keadaan saat itu, yang genting dan memaksa serta memerlukan tindakan cepat untuk kemudian diselesaikan. Salah satu masalah yang tidak mungkin dapat untuk diabaikan bahkan dapat saja mengancam eksistensi negara Indonesia yang baru berdiri
I Gusti Ngurah Santika, SPd
76
tersebut, adalah adanya suatu propaganda dari NICA bahwa negara Indonesia adalah negara buatan Jepang yang tidak bersifat demokratis. Di mana propaganda NICA bahwa bangsa Indonesia adalah negara bentukan Jepang yang tidak demokratis dilancarkan semakin intensif dalam pergaulan internasional, bahkan dalam hal ini menurut NICA sendiri bahwa bangsa Indonesia harus dihancurkan. Dengan adanya propaganda dari Belanda tersebut, tentunya membuat gerah para pemimpin bangsa. Tidak lain dikarenakan tentunya para pemimpin bangsa ini mengetahui persis apa yang sebenarnya kemudian menjadi niat Belanda itu, yaitu untuk menduduki bangsa Indonesia atau dengan kata lain, dapat menjajah bangsa Indonesia kembali. Tidak ada hal lain lagi yang mungkin dapat dilakukan oleh para pemimpin bangsa Indonesia, selain mengambil berbagai tindakan untuk kemudian mengatasi masalah yang timbul tersebut, walaupun tentunya akan berpotensi untuk bertentangan dengan UUD 1945. Tindakan tersebut perlu untuk dilakukan, dikarenakan intensifnya propaganda yang datang dari Belanda dalam pergaulan Internasional, dengan tujuan untuk mendapatkan sebanyak mungkin dukungan, guna menghancurkan bangsa Indonesia yang baru merdeka itu. Kecuali itu, ditambah adanya propaganda Belanda lainnya yang mengatakan bangsa Indonesia bukanlah sebagai bangsa yang demokratis, hal mana dikarenakan sebelumnya ada sebuah usul yang datang dari Achmad Subardjo untuk membentuk sebuah partai negara, yaitu PNI yang nantinya akan dipimpin oleh Soekarno. Terkait dengan adanya usul untuk pembentukan sebuah partai tunggal, menurut Safaat (2011;125) bahwa pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan rapat yang salah satu keputusannya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia. PNI diharapkan menjadi partai tunggal atau partai negara dan sebagai pelopor dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun, karena semakin intensifnya propaganda Belanda tentang tidak demokratisnya Indonesia dalam dunia internasional, misalnya menyatakan bahwa Indonesia hanya mendasarkan pada satu partai politik, yaitu partai negara, sehingga seolah-olah merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya otoriter. Menanggapi hal tersebut, para pemimpin bangsa cepat mengambil langkah, dengan membentuk aturan yang kemudian akan menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara demokratis, yang nantinya ditandai dengan sistem kepartaian, yaitu menganut sistem multipartai. Aturan sebagaimana dimaksud tersebut adalah Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang kebebasan rakyat untuk mendirikan partai politik. Namun, tentunya kebebasan untuk membentuk partai politik bukanlah tanpa batas, karena di dalamnya dinyatakan bahwa partai politik yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Maklumat tersebut, adalah partai politik yang tentunya mendukung bangsa Indonesia dalam usahanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta menghadapi revolusi yang sedang bergolak, dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
77
berhadapan dengan keinginan penjajah untuk menduduki Indonesia kembali. Tindak lanjut kemudian oleh pemimpin bangsa setelah dianutnya sistem multipartai berdasarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Ternyata setelah itu, disusul kemudian dengan adanya usul dari BP-KNIP untuk membentuk sistem pemerintahan parlementer yang berarti mengubah secara tidak langsung terhadap ketentuan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan yang dianut seharusnya pada waktu itu yaitu sistem pemerintahan presidensial (quasi presidensial). Berdasarkan usul BP-KNIP tersebut maka pada tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah yang mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer dengan menunjuk Hatta sebagai perdana menteri parlementer pertama (Mahmud MD,2010;26). Apa yang sebelumnya dinyatakan oleh Mahmud MD memang benar bahwa setelah keluarnya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945 tersebut, sistem pemerintahan Indonesia kemudian berubah dari sistem pemerintahan presidensial (quasi presidensial) selanjutnya menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hanya saja dalam hal ini, perdana menteri sebagaimana dimaksudkan oleh Mahmud MD sebagai menteri pertama dalam sistem parlementer tersebut adalah kurang tepat. Hal mana dikarenakan pada waktu itu, perdana menteri pertama sistem pemerintahan parlementer berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 adalah tunjukan Soekarno sendiri, yaitu Sjahrir yang tentunya tidak memiliki hubungan dengan Jepang. Dikarenakan pada waktu ini, Soekarno sendiri dicela oleh Sekutu sebagai kolaborator Jepang. Dua ketentuan di atas (Maklumat Pemerintah No. 3 November dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945) ternyata memiliki hubungan yang erat dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, pertama berkaitan dengan berdirinya partai-partai untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa dan negara yang sifatnya demokratis. Hal ini tidak lain dikarenakan oleh persepsi Barat yang cukup keliru tentang negara demokratis adalah negara yang kemudian hanya memiliki jumlah partai banyak (lebih dari satu partai). Maka mulai saat itulah, kemudian disusul dengan banyaknya muncul partai-partai yang selanjutnya dibentuk oleh rakyat bertujuan untuk ikut terlibat serta berpartisipasi dalam membangun bangsa Indonesia, melalui perjuangan revolusi. Seraya membuktikan kepada Barat bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang, dimana Jepang pada dasarnya merupakan negara fasis, dikarenakan sistem pemerintahan Jepang sendiri hanya berdasarkan pada sistem satu partai. Tidak adanya partai politik setelah kemerdekaan bukan berarti tidak ada keinginan untuk mendirikannya kemudian. Hal ini dikarenakan sebelumnya ada larangan daripada penjajah yang sangat intensif berupa paksaan, bahkan pada waktu itu penjajah melarang setiap
I Gusti Ngurah Santika, SPd
78
kegiatan yang pada dasarnya berbau politik. Seperti terlihat sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa pemerintahan bala tentara Jepang, semua organisasi politik dibubarkan, sehingga praktis pada saat Poklamasi kemerdekaan secara formal tidak ada partai politik (Kantaprawira,1990;80). Dengan adanya Maklumat Pemerintah tentang pendirian partai politik, tentunya pemerintah kemudian berharap bahwa partai-partai yang dibentuk nantinya dapat memperkuat perjuangan bangsa Indonesia dalam usaha menghadapi Belanda, atau dengan kata lain, diharapkan keberadaan partai politik mampu mempersatukan segala kekuatan yang ada. Perlu diketahui bahwa UUD 1945 pada waktu itu tidaklah pernah menyebut-nyebut nama partai politik. Karena memang dalam ketentuan UUD 1945 pada kenyataannya tidak terdapat ketentuan satupun yang kemudian mengatur tentang keberadaan daripada partai politik. Ketentuan tentang mendirikan partai politik akhirnya mendapatkan angin yang lebih segar, ketika dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang kemudian disusul dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang pada dasarnya telah mengubah sistem pemerintahan presidensial (quasi) yang sebenarnya memang secara tegas telah ditentukan dalam UUD 1945. Sistem pemerintahan sebagaimana dimaksudkan di atas pada waktu itu dalam UUD 1945 adalah sistem pemerintahan Presidensial (quasi presidensial), sedangkan dengan adanya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945 telah meberubahnya menjadi sistem pemerintahan parlementer. Otomatis dengan adanya ketentuan ini, telah memisahkan kedudukan antara Presiden sebagai kepala negara dengan kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang selanjutnya akan dipegang oleh perdana menteri. Melalui pemindahan ke sistem parlementer, maka secara otomatis jabatan kepala negara (presiden) dipisahkan dari jabatan kepala pemerintahan (perdana menteri). Selain dari memperluas basis perjuangan karena mengikutsertakan semua kekuatan anti fasis dalam perjuangan kemerdekaan, perubahan ini juga memungkinkan untuk tetap mempertahankan Presiden Soekarno sebagai simbol kepala negara dan pemersatu rakyat (Budiardjo,2008;199). Dengan demikian, pada dasarnya ada dua ketentuan yang sebenarnya telah mengubah praktek ketatanegaraan, hal mana berarti berlawanan dengan apa yang kemudian telah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945, yaitu berkaitan dengan kekuasaan Presiden. Lebih lanjut terkait keluarnya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945, maka Thoha (2011;115) berpendapat bahwa inilah sebenarnya penyimpangan pertama dari UUD 1945, karena undang-undang dasar ini menetapkan mengikuti pemerintahan presidensial akan tetapi kenyataannya diarahkan berdasarkan maklumat ke sistem parlementer. Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November dan Maklumat Wakil Presiden Nomor X, bukan saja kekuasaan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
79
Presiden menjadi sangat berkurang, akan tetapi sistem pemerintahan pun menjadi berubah (Soemantri,1985;16). Mulai saat itu kabinet kedua dan seterusnya dijabat oleh orang-orang partai politik dan bertanggungjawab kepada parlemen, sebagai penganut daripada sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan sistem pemerintahan parlementer, Pemerintahan dijalankan oleh kabinet, yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pembentukan kabinet dilakukan dengan persetujuan KNIP sebagai parlemen Indonesia saat itu. Menteri sebagai satu kesatuan kabinet maupun secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada KNIP. KNIP menentukan pembentukan dan jatuhnya kabinet (Safaat,2011;133). Nantinya, ternyata dalam sejarah perjalanannya dengan sistem pemerintahan parlementer, kemudian ditambah dengan banyaknya jumlah partai politik, yang disertai dengan kurangnya integritas partai politik dalam menegakan kehidupan yang demokratis, telah pula menjadi penyebab tidak terjaganya stabilitas pemerintahan untuk menjalankan program kerjanya. Dengan adanya beberapa ketentuan di luar UUD 1945 berupa Maklumat, baik oleh Wakil Presiden maupun oleh Soekarno tersebut, tentunya memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahkan dapat menjungkirbalikan semua kekuasaan Presiden dari semula yang sebelumnya diberikan oleh ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, sampai akhirnya semua ketentuan yang berhubungan dengan sistem pemerintahan negara, seperti apa yang diatur oleh UUD 1945. Begitu besarnya kekuasaan oleh Presiden yang sebelumnya diberikan oleh Pasal IV Aturan Peralihan dan UUD 1945 itu sendiri. Bahkan dengan adanya ketentuan tersebut dalam UUD, dapatlah kemudian dikatakan bahwa seorang Presiden dapat berbuat apa saja terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun setidaknya, dengan adanya perubahan terhadap sistem pemerintahan, dari sistem pemerintahan presidensial (quasi) kemudian menjadi sistem pemerintahan parlementer, setidaknya telah membawa dampak yang sangat besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Di mana menurut Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 itu, maksud yang paling penting adalah tanggungjawab pemerintahan berada pada menteri. Otomatis menurut Soehino (2010;38) bahwa pada hari tanggal 14 November 1945, terjadilah perubahan sistem pemerintahan negara, dari sistem pemerintahan kabinet presidensiil berubah menjadi sistem pemerintahan negara kabinet parlementer. Sebenarnya dalam rapat plenonya ketiga di Jakarta pada tanggal 25-27 November 1945, KNIP menerima keputusan ini dan memberi dukungan kepada kebinet Sjahrir. Dengan demikian, praktis posisi Presiden dipisahkan dari posisi kepala eksekutif (Anwar,1998). Dengan diterimanya usul Badan Pekerja KNIP itu, kabinet presidensial di bawah pimpinan Presiden Soekarno meletakan jabatan pada tanggal 14 November 1945 dan diganti oleh kabinet baru dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri (Kusnardi dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
80
Sarigih,1986139). Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945, merupakan Maklumat berisi dua hal yang sangat penting, yaitu susunan Kabinet St. Sjahrir yang pertama dan pertanggungjawabannya. Menurut maklumat itu tanggungjawab berada di tangan menteri. Ini berarti, bahwa dengan keluarnya Maklumat Pemerintah di atas, telah terjadi perubahan sistem pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain telah terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (Soemantri,1985). Sebenarnya, jika kita lihat kembali dalam ketentuan undang-undang dasar ternyata tidaklah ada perubahan, dikarenakan memang tidak ada bunyi dari ketentuan UUD 1945 yang berubah. Namun, jika kemudian kita lihat kembali dalam kenyataan ataupun pada praktik ketatanegaraan, dapatlah kemudian kita lihat perbedaan antara apa yang memang tertulis dalam UUD 1945 dan nampak dalam praktik, terkait dengan sistem pemerintahan. Dengan demikian, ketentuan UUD 1945 tidak mengalami perubahan, hanya saja praktiklah yang kemudian menyimpang dari UUD 1945 berkaitan dengan sistem pemerintahan dari presidensialisme yang kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan paparan tersebut di atas, Suny (1986;40) selanjutnya menyatakan bahwa baik Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945 atas dasar Aturan-Aturan Peralihan dan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konvensi-konvensi ketatanegaraan yang berasal dari ketentuan-ketentuan yang berdasarkan atas persetujuan yang dinyatakan (express-agreement) antara Presiden dan Badan Pekerja (KNIP). Dengan demikian, Suny menyatakan bahwa Maklumat Pemerintah 14 November 1945 merupakan suatu konvensi ketatanegaraan (convention of the constitution). Pertanyaannya adalah apakah suatu konvensi dapat bertentangan dengan UUD 1945, yang mana UUD 1945 pada dasarnya merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara?. Lagipula, konvensi merupakan suatu ajaran moral yang tentunya mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam arti secara pribadi merupakan suatu pedoman yang harus dipatuhi. Sebenarnya apa yang sebelumnya dinyatakan oleh Suny adalah sesuai dengan pendapat dari Wheare dalam Budiardjo (2008;180) yang menyatakan bahwa dapat saja suatu peristiwa disebut konvensi tanpa sebelumnya telah terjadi, asal ada persetujuan yang jelas (express egreement); ia tidak lahir dari kebiasaan dan tidak pula mempunyai sejarah sebelumnya. Oleh karenanya, apakah suatu Maklumat yang merupakan suatu kesepakatan antara pemerintah dengan KNIP yang mana adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 haruskah diikuti? Walaupun tindakan yang kemudian dilakukan oleh para the founding father adalah menyimpang jika dilihat dari sudut hukum konstitusi yang berlaku. Namun perlu diketahui bahwa hal ini merupakan suatu respon
I Gusti Ngurah Santika, SPd
81
terhadap keadaan yang sifatnya genting dan memaksa pada saat waktu itu. Dalam kenyataannya terkait dengan ketentuan tersebut di atas terutama prakteknya ternyata dipatuhi (mirip dengan istilah dalam hukum pidana yaitu Overmacht dalam Pasal 48 KUHP, yang tentunya menghilangkan sifat tindak pidana yang dilakukan). Dengan demikian, tidak kemudian dapat dipersalahkan kepada pemimpin bangsa, terkait langkah yang kemudian diambil pada waktu itu, yang mana tindakan tersebut ternyata bertentangan dengan apa yang kemudian diatur dalam UUD 1945, dikarenakan oleh keadaan memaksa (overmacht) sebagaimana dimaksudkan di atas. Terkait dengan The Convention of the constitution sebagaimana dinyatakan oleh Suny di atas, maka menurut Asshiddiqie (2006;13) mencakup: (a) kebiasaan-kebiasaan (habits), (b) tradisi-tradisi (tradition), (c) adat istiadat (custom), (4) praktek-praktek (practices and usages). Dapatlah dikatakan bahwa pada periode ini menurut Muhammad (1986;187) merupakan revolusi fisik antara tahun 1945 dan tahun 1950 dan beberapa tahun pertama sesudah tahun 1950 ituyaitu pada zaman yang kita perlukan untuk mengkonsolidasi segala yang telah kita peroleh sebagai hasil revolusi fisik antara tahun 1945 dan tahun 1950. Sehingga apa yang diharapkan oleh aturan formal yang berlaku tentunya tidak dapat dijalankan sepenuhnya, yaitu sesuai dengan apa yang benar-benar tercantum dalam teks UUD 1945, hal mana tentunya telah disadari pula oleh para pendiri bangsa, yang lebih mempertimbangkan untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru dicapainya, ketimbang hanya mengikuti prosedural formal semata. Bagi para pendiri negara itu sendiri, kemerdekaan adalah segala-galanya, sedangkan untuk konstitusi barulah kemudian akan berlaku, jika saja kemerdekaan benar-benar dapat dicapai dan dipertahankan. Tanpa itu, konstitusi hanyalah sebuah secarik kertas yang tidak berharga tentunya karena tidak dapat berlaku. Seperti apa yang kemudian dinyatakan oleh Mahmud MD (2001;90) di bawah ini, yang pada dasarnya dalam pernyataannya terkait dengan perjalanan daripada UUD 1945 yang sebelumnya mengalami pasang surut. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam gerak pelaksanaannya juga mengalami pasang surut, pasang naik dan timbul tenggelam. Pasang naik dan pasang surut itu bisa digambarkan bahwa pada suatu saat Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku, tapi pada saat yang lain dinyatakan tidak berlaku lagi atau bisa juga, Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan berlaku secara resmi tapi dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
82
praktik pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan atau ditinggalkannya asas-asas yang terkandung di dalamnya. Hal yang senada selanjutnya dinyatakan oleh Joeniarto (1996;46) bahwa undangundang dasar adalah undang-undang dasar revolusi, undang-undang dasar perjuangan. Sebagaimana hal dengan revolusinya, maka Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pula masa-masa pasang surut. Pernyataan demikian dapat diketahui dalam sejarah perjalanannya, mulai ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi, sampai kemudian UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi dalam salah satu negara bagian, yang karena digantikan dengan KRIS sebagai konstitusi serikat, yang pada dasarnya mengubah bentuk negara kesatuan. Dengan demikian, sebenarnya UUD 1945 memang belum sepenuhnya dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Semua itu terjadi dikarenakan berbagai keadaan yang kemudian menyebabkan untuk tidak memberlakukan UUD 1945. Dan hal itu, juga tentunya mendapatkan dukungan yang luas baik oleh para pendiri negara serta dapat diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga diawali dengan adanya sebuah kesepakatan politik, yang kemudian menjadi yuridis (yuritische geltung), sampai pada akhirnya diterima secara sosiologis (soziologische geltung) serta tentunya juga kekuatan keberlakuannya secara filosofis (filosopische geltung). Tentunya penerimaan terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi kemudian terhadap UUD 1945 pada masa-masa revolusi, karena memang berguna dan diakui kegunaannya (Anarkennungstheori) oleh rakyat, hal ini merupakan salah satu tinjauan dari sudut keberlakuan suatu hukum, tentunya termasuk pula konstitusi yang pada dasarnya sebagai sebuah hukum dasar. Tentunya jika tinjau daripada kekuatan berlaku secara sosiologis (soziologische geltung) itu sendiri, dapat dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu : a. Menurut teori kekuatan (Mahchtstheori) hukum yang mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlaku oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh masyarakat. b. Menurut teori pengakuan (Anarkennungstheori) hukum yang mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat (Mertokusumo,1996;81). Sehingga dari teori sosiologis (soziologische geltung), maka berkaitan dengan tindakan yang sebelumnya diambil oleh para pendiri negara, walaupun pada dasarnya bertentangan dengan UUD 1945. Namun, bila ditinjau kembali dari segi sosiologis, dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
83
kenyataannya telah mendapatkan dukungan luas dari rakyat Indonesia. Setidaknya karena hal tersebutlah, yang kemudian menyebabkan adanya sebuah pengakuan (Anarkennungstheori) dari rakyat terhadap kegunaan daripada berbagai bentuk penyimpangan tersebut. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 (RIS) Beberapa saat setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, pihak Belanda berusaha untuk menguasai kembali bekas jajahannya dengan mendompleng Angkatan Perang Inggris yang diberi tugas oleh pihak Sekutu untuk menduduki daerah-daerah yang dikuasai oleh angkatan Perang Jepang. Usaha Belanda kembali ke Indonesia membawa akibat terjadinya konflik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda (Soemantri,1985;5). Bahkan, berbagai usaha berupa percobaan untuk kemudian menghapuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan. Sehingga dengan demikian Belanda sangat berharap untuk dapat menjajah kembali Indonesia. Usaha pertama yang sebelumnya dilakukan oleh Belanda untuk menguasai Indonesia, yaitu berupa Agresi Militer pertamanya pada tanggal 21 Juli 1947 yang tentunya telah menghianati perjanjian Linggarjati (Rindjin,2009;302). Kemudian disusul dengan peristiwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1948, dimana pada saat Pemerintah Belanda melancarkan aksi militer kedua (Agung,1995). Keinginan Belanda yang bertujuan untuk menjajah kembali bangsa Indonesia, tentunya mendapat perlawanan yang sengit dari segenap komponen bangsa Indonesia. Dengan penuh keyakinan, disertai cinta dan semangat yang tinggi untuk tetap mempertahankan tanah air (nationalism), segenap komponen bangsa dengan sadar mengadakan perlawanan, baik dengan senjata maupun dengan jalur diplomasi untuk menghadapi keinginan Belanda tersebut. Bahkan, di berbagai daerah telah meletus pertempuran antara Belanda di satu pihak dengan Indonesia dipihak lain, yang berakibat telah menimbulkan korban yang tidak sedikit daripada kedua belak pihak tersebut. Dari pihak Belanda, yaitu Van Mook mempunyai ide untuk menghancurkan negara NKRI secara perlahan-lahan, yaitu dengan cara memecah belahnya menjadi negara-negara kecil. Taktik ini bisa kemudian dikatakan dengan istilah devide et impera, sehingga dengan hancurnya negara republik Indonesia otomatis Belanda akan dapat kembali menjajah Indonesia. Dalam hal ini, Kansil (1985;129) menyatakan bahwa di samping kekerasan senjata yang dilancarkan terhadap RI, Belanda menjalankan politik federalismus, sebagai politik devide et impera untuk memecah-belah persatuan bangsa. Hal tersebut telah memicu terjadinya berbagai pertempuran antara Indonesia dan Belanda, yang pada akhirnya mengundang perhatian dunia khususnya PBB yang merasa prihatin terhadap terjadinya peristiwa
I Gusti Ngurah Santika, SPd
84
tersebut, sehingga atas desakannya agar Indonesia dan Belanda kemudian sesegera mungkin melakukan perundingan untuk mengakhir konflik antara Indonesia dan Belanda. Paling tidak untuk sementara waktu, tidak terjadi insiden tembak menembak di antara kedua bela pihak dengan tujuan untuk mengurangi korban. Dari berbagai usaha yang kemudian dilakukan oleh Indonesia dan Belanda baik yang dilakukan atas usaha kedua negara tersebut maupun atas tekanan dari dunia internasional, akhirnya disepakatilah suatu perundingan yang selanjutnya dinamakan dengan Konperensi Meja Bundar. Terkait dengan hasil dari konperensi tersebut, terutama yang menyangkut dalam bidang ketatanegaraan, Djamali (2008;114) kemdian menyatakan pendapatnya bahwa. Salah satu hasil konferensi yang menyangkut bidang ketatanegaran adalah berubahnya bentuk negara republik Indonesia dari bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau berbentuk federal. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat sebagai konstitusinya. Menurut sejarahnya, pembentukan konstitusi RIS dilakukan sejak Konperensi antar Indonesia berlangsung dan pertemuan Jakarta tanggal 31 Juli -2 Agustus 1949 yang kemudian dilanjutkan di Belanda selama Konperensi Meja Bundar berlangsung. Setelah adanya perjanjian Meja Bundar antara Belanda dengan Indonesia, maka disetujui bahwa negara Indonesia tidak lagi berbentuk kesatuan, melainkan akan berbentuk federal. Negara federal mulai berdiri, yang ditandai dengan disahkan Konstitusi RIS, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Menurut Pasal 2 konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah bersama dari : a. Negara Republik Indonesia dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renvile tanggal 14 Januari 1948, yaitu Negara Indonesia Timur. Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta. Negara Jawa Timur. Negara Madura. Negara Sumatra Timur, dengan pengertian bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu sehubungan dengan Negara Sumatra Timur tetap berlaku.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
85
b. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri adalah sebagai berikut: Jawa Tengah. Bangka. Riau Kalimantan Barat (daerah istimewa). Dayak Besar. Daerah Banjar Kalimantan Tenggara. Kalimantan Timur. a dan b adalah daerah-daerah bagian yang dengan kegembiraan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat, berdasarkan yang ditetapkan dalam konstitusi ini. c. Daerahdaerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian. Pemerintah Indonesia di Yogyakarta sebagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat mempunyai program kabinet, yang terpenting adalah : meneruskan perjuangan untuk mencapai Negara Kesatuan yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia dan dimaksudkan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 (Prodjodikoro, 2008;10-11). Jika kita ingat kembali, dapat dikatakan bahwa Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah sebuah negara federal, yang menggabungkan lima belas negara bagian yang telah didirikan Belanda selama tiga tahun sebelumnya di wilayah yang didudukinya, sebagai bagian usaha melawan Republik Indonesia (RI) yang revolusioner itu. Namun, Republik revolusioner yang menjadi anggota keenam belas RIS inilah yang mendominasi struktur federal. Sehingga yang mereka yang naik ke tampuk kekuasaan pada bulan Desember 1949 adalah para pemimpin yang berkuasa dari masa revolusi. Soekarno menjadi presiden dan Hatta menjadi perdana menteri Republik baru itu (Feit,2001;10). Walaupun bentuk negara adalah serikat, pada dasarnya tidaklah kemudian dapat mengurangi semangat juang bangsa Indonesia dalam membentuk negara kesatuan sebagaimana saat diproklamasikan.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
86
Dengan demikian, kedudukan UUD 1945 setelah keluarnya Konstitusi RIS sebagai hasil daripada KMB, menurut Rato (2009;145-146) bahwa UUD 1945 tidak diberlakukan sejak berlakunya Konstitusi RIS (pada saat itu UUD 1945 hanya berlaku di Republik Indonesia), sebagai negara bagian RIS dengan ibu kotanya Jogyakarta. Otomatis kekuatan mengikatnya UUD 1945 tidak seperti sebelumnya, yang mana tentunya mengikat seluruh wilayah NKRI, sedangkan untuk sekarang RI hanyalah merupakan sebuah negara bagian belaka, yang mana tentunya UUD 1945 hanya mengikat negara bagian tersebut saja. Bahkan dalam hal ini, Kansil (1986;54) berpendapat bahwa pada masa Republik Indonesia Serikat, UUD 1945 menjadi turun derajatnya dan berkurang wilayah berlakunya, oleh karena UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia. Kesediaan bangsa Indonesia untuk menerima hasil konferensi di atas adalah, hanya sebuah taktik saja daripada bangsa Indonesia, untuk selanjutnya dapat membentuk negara kesatuan, sebagaimana pada saat diproklamasikan, seperti apa yang sebelumnya dinyatakan oleh Prodjodikoro tersebut di atas. Dengan demikian sasaran yang harus dicapai dengan KMB ialah mengakhiri segala pertikaian dan pertentangan dengan pihak Belanda di segala lapangan kenegaraan: politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan(Purbopranoto,1981;78). Dapat dikatakan kemudian bahwa Konperensi Meja Bundar merupakan sebuaah taktik dari pihak Indonesia, agar dapat terlepas dari berbagai pertikaian yang berkepanjangan dikedua belah pihak. Langkah ini merupakan sebuah kebijakan yang kemudian diambil oleh pendiri negara pada waktu, yang pada dasarnya kebijakan tersebut lebih mendahulukan kepentingan rakyat, agar dikemudian hari tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan akibat konflik tersebut. Lagipula dalam hal ini, Konstitusi RIS adalah hasil maksimal yang bisa dicapai oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berjuang di pihak Republik, guna mewujudkan keutuhan dan kesatuan bangsa dan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke (Damal,1986;35). Bagi bangsa Indonesia bentuk negara serikat hanyalah merupakan bentuk kesepakatan politik yang hanya berlaku untuk sementara waktu saja, yang nantinya akan diperjuangkan kembali dengan jalur konstitusional yang telah disediakan. Sehingga sampai pada tujuan akhir, yaitu untuk mencapai negara kesatuan sebagaimana perjuangan awal bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu untuk membentuk negara kesatuan yang dilandasi rasa persatuan. Artinya, dengan terbentuknya RIS melalui Konperensi Meja Bundar, belumlah berarti bahwa perjuangan bangsa Indonesia berakhir sampai di sini. Bahkan dengan terbentuknya RIS merupakan titik tolak awal daripada perjuangan untuk kembalinya Indonesia dalam menyatukan bagianbagian wilayah Indonesia sehingga menjadi negara yang berbentuk kesatuan, sebagaimana
I Gusti Ngurah Santika, SPd
87
yang sebelumnya telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal mana adalah sesuai dengan pernyataan dari Budiardjo (2008;281) yang menyatakan karena bentuk negara federal ini hanya dianggap sebagai suatu adempauze, saat bernapas, dalam perjuangan kita untuk menyelenggarakan terwujudnya negara kesatuan yang merdeka. Hal ini terlihat jelas ketika pada awal permulaan tahun 1950 timbul desakan-desakan rakyat untuk membubarkan negara-negara bagian (Attamimi,1990;258). Dan akhirnya tidak lebih dari 8 bulan perjalanannya, bentuk negara serikat dengan dasar hukumnya KRIS dinyatakan tidak berlaku. Tidak lain dikarenakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, dengan UUD Sementara 1950 sebagai dasar hukumnya. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidaklah dimaksudkan sebagai konstitusi yang bersifat tetap, melainkan merupakan konstitusi yang pada dasarnya hanya bersifat sementara, ketentuan tersebut dapatlah kemudian dilihat dari ketentuan Pasal 186 KRIS. Intinya dalam ketentuan tersebut menyatakan, bahwa konstitusi Republik Indonesia Serikat bersifat sementara, yang kemudian akan diganti dengan konstitusi yang bersifat tetap, sedangkan konstitusi tetap tersebut dibuat oleh sebuah badan yang bernama Konstituante. Namun, pada kenyataan sampai dengan berakhirnya KRIS, badan sebagaimana dimaksudkan oleh KRIS yang nantinya akan membuat konstitusi baru, yang selanjutnya akan menggantikan KRIS belumlah dapat dibentuk. Sistem pemerintahan yang dianut oleh KRIS adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana tanggungjawab utama pemerintahan terletak pada pundak perdana menteri dan menteri sebagai kabinet. Namun, dalam sistem pemerintahan berdasarkan KRIS, tidak ada kabinet yang jatuh dikarenakan mosi tidak percaya dari parlemen. Hal ini tidak lain dikarenakan, belum adanya lembaga perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya benarbenar dipilih melalui pemilihan umum, untuk dapat mewakili kehendak rakyat, sehingga dengan demikian tidaklah kemudian berhak untuk membubarkan kabinet. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 (Liberal) Akhirnya bentuk negara federal yang merupakan hasil rekayasa Van Mook ternyata tidaklah berumur lama, begitu juga dengan dasar hukum federasi tersebut yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan ternyata hanya dalam waktu delapan bulan saja bentuk federal sudah dibatalkan dan dalam bulan Agustus 1950 diganti dengan bentuk negara kesatuan (Budiardjo,2008;281). Sejak Semula sudah terang bahwa rakyat dari daerahdaerah bagian diseluruh Indonesia menghendaki pembentukan suatu negara kesatuan. Di
I Gusti Ngurah Santika, SPd
88
beberapa tempat timbul demonstrasi-demonstrasi yang menyatakan keinginan mereka untuk merubah bentuk negara federasi menjadi negara kesatuan (Suny,1986). Dari kenyataan itu jelas bahwa rakyat Indonesia tidak menghendaki lagi bentuk negara federal melainkan bentuk negara kesatuan (Soemantri,1992;139). Hal ini dapatlah kemudian kita ketahui bahwa awal mula daripada perjuangan bangsa ini adalah untuk merebut kemerdekaan dari penjajah dengan tujuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan, yang tentunya bertumpu pula pada semangat persatuan, yaitu adanya kehendak bersama dan nasib sepenanggungan, yakni sebagai bangsa yang terjajah. Maka tiada lain, hanya dengan membentuk negara kesatuan kembali, sehingga rakyat tidak lagi melakukan berbagai bentuk tindakan yang kemudian dapat digolongkan sebagai tindakan yang anarkis. Padahal yang menjadi akar permasalahannya adalah hanya menginginkan Indonesia untuk kembali menjadi negara kesatuan, dengan mengubah bentuk federal yang sebenarnya hanyalah merupakan rekayasa Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan tampaknya keinginan rakyat tersebut, akan cepat dapat diwujudkan oleh pemimpin bangsa. Tidak lain dikarenakan berbagai situasi yang terjadi di berbagai daerah, yang pada dasarnya benar-benar mengancam keberadaan negara ini. Sehingga, tidak ada pertimbangan lagi untuk tetap mempertahankan bentuk negara serikat tersebut. Menurut Prodjodikoro (2008;11) bahwa dalam beberapa bulan saja berturut-berturut hampir semua negara (daerah) bagian diluar Negara Bagian Republik Indonesia, sama menggabungkan diri pada Republik Indonesia sehingga pada pertengahan tahun 1950 Republik Indonesia serikat hanya terdiri atas tiga negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Karena tuntutan yang kuat untuk kembali ke negara kesatuan, akhirnya berdasarkan Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 ditetapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950 (Safaat,2011;133-134). Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali kepada negara kesatuan dengan memberlakukan UUD Sementara 1950 (Mahkamah Konstitusi,2010;59,Jilid IV). Dengan disahkannya UUDS 1950, maka bentuk negara kesatuan kembali seperti setelah kemerdekaan, namun dikurangi Papua Barat (Irian Jaya). Jika ditinjau dari sudut ketatanegaraan dalam masa ini disebut dengan demokrasi liberal ditandai oleh dilaksanakannya UUD Sementara 1950, yang ditetapkan berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950, sebagai dasar negara kesatuan II, Republik Indonesia (Mudyahardjo,2010;385). Dasar yang kemudian dijadikan sebagai tolok ukur, untuk menyatakan bahwa NKRI adalah sebuah negara demokrasi yang sifatnya liberal oleh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
89
Mudyahardjo, yaitu UUDS 1950. Kalaulah kemudian kata liberal diterjemahkan berarti kebebasan. Dengan kata lain, bahwa istilah kebebasan berarti selalu mengutamakan kebebasan individu di atas segala kepentingan yang lain. Dengan kata lain, kepentingan yang bersifat pribadi tersebut merupakan kepentingan yang tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Tentunya bila saja kepentingan individu tersebut direalisasikan kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan diperoleh bentuknya yang konkret, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Periode demokrasi parlementer (1950-1957) merupakan periode ketidakpastian yang ditandai oleh tidak tercapainya konsensus mengenai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang hendak dicapai dan pemberontakan-pemberontakan daerah yang dilandasi oleh agama etnik dan ketidakpuasan terhadap kelemahan pusat (MacAndrews dan Amal,2003;13). Hal mana dapatlah ketahui dari berbagai gerakan yang sebelumnya dilakukan oleh daerah, untuk mencoba memisahkan diri dari NKRI, dikarenakan adanya rasa ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat, terutama terkait dengan konsep keadilan. Selain hal tersebut, yang selanjutnya menjadi sorotan utama dalam periode ini adalah stabilitas pemerintahan yang sangat lemah. Ditandai pula oleh sering kali jatuhnya kabinet karena adanya mosi tidak percaya daripada parlemen. Berkaitan dengan sistem ketatanegaraan, jelaslah dapat diketahui bahwa sebenarnya konsep yang dianut oleh KRIS dan UUDS adalah berbeda satu sama lainnya. Apabila kita membandingkan pokok isi UUD Sementara ini dengan pokok isi Konstitusi RIS. Maka perbedaannya, kecuali perbedaan yang terbawa oleh sebab Konstitusi RIS berbentuk federasi, sedang UUD Sementara ini berbentuk unitaristis (Soepomo,1954; 13). Pendapat yang sama tentang berlakunya UUD Sementara 1950 yang telah membawa akibat bagi terbentuk negara kesatuan, juga dinyatakan kembali oleh Wiranata (2005;42) bahwa akibat kondisi politik waktu pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 karena berbentuk negara Republik juga mengalami perombakan. Perombakan sebagaimana dimaksud adalah berubahnya bentuk negara dari negara serikat sebagaimana dalam KRIS, kemudian menjadi negara kesatuan seperti dalam UUDS 1950. Jika dipandang dari sudut sejarah maka Undang-Undang Dasar 1950 ini telah merupakan suatu perbaikan dari pada dua Undang-Undang Dasar yang berlaku lebih dulu, tetapi tidak hanya Undang-Undang Dasar 1945 dan 1949, tapi Undang-Undang Dasar 1950 pun mengakui diri sebagai sementara karena tidak dibentuk oleh wakil-wakil yang terpilih oleh rakyat dalam pemilihan umum (Pringgodigdo,1981;15). Didasari pemikiran yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
90
bersifat luhur, bahwa idealnya sebuah konstitusi harusnya dibuat oleh sebuah lembaga perwakilan rakyat, yang anggota-anggotanya memang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga konstitusi yang dibentuk kemudian adalah benar-benar merupakan kehendak rakyat serta merupakan konstitusi yang berwatak demokratis. Namun setidaknya, dengan adanya perubahan terhadap bentuk negara serikat kemudian berubah menjadi negara kesatuan, yang bertujuan untuk memenuhi kehendak rakyat berdaulat, tentunya sudah cukup membuktikan bahwa UUDS 1950 adalah undang-undang yang berwatak demokratis. Dengan demikian, UUDS 1950 sedikit tidaknya telah memenuhi pula keinginan rakyat yang berdaulat terutama untuk membentuk sebuah negara dengan bentuk kesatuan. Terkait dengan bentuk negara kesatuan yang akan dibentuk pada waktu itu, Soepomo (1954;8) menyatakan bahwa negara kesatuan akan diperdapat dengan mengubah Konstitusi RIS sedemikian rupa, sehingga esentialia UUD Republik Indonesia, antara lain pasal-pasal 27, 29, dan 33 ditambah dengan bagianbagian yang baik dari Konstitusi RIS termasuk di dalamnya. Ini membuktikan bahwa dengan dirubahnya KRIS 1949 menjadi UUDS 1950, hanyalah menyesuaikan beberapa ketentuan yang ada di dalamnya, agar selanjutnya sesuai dengan bentuk negara kesatuan yang kemudian akan dibentuk, tentunya berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yang mana pada dasarnya KRIS 1949 menganut bentuk negara serikat. Merupakan suatu agenda utama yang memang sangat dikehendaki untuk memenuhi tuntutan rakyat secepatnya, serta dengan suatu pertimbangan yang bisa dibilang matang, bahwa UUDS 1950 yang dibentuk tersebut bukanlah undang-undang yang bersifat tetap, melainkan suatu undang-undang dasar yang masih bersifat sementara (intrim). Dan tentunya nanti akan dibuat suatu konstitusi yang baru serta bersifat tetap. Bahkan telah ditentukan akan dibuat oleh lembaga negara yang dibentuk dan anggota-anggota yang duduk di dalamnya dipilih oleh rakyat sendiri, sehingga konstitusi yang disusun benar-benarlah merupakan suatu cerminan daripada kedaulatan rakyat. Berkaitan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer, yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet atau dewan menteri yang terjadi silih berganti. Penyebab utama daripada jatuh bangunnya kabinet/dewan menteri tersebut, tidak lain disebabkan oleh sistem pemerintahan yang dianut, yaitu sistem pemerintahan parlementer, yang pada dasarnya mengutamakan tanggungjawab pemerintahan oleh kabinet kepada lembaga legislatif (parlemen). Mungkin inilah yang kemudian bisa dikatakan sebagai ciri daripada liberalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang memang mengutamakan kepentingan pribadi di atas segala-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
91
galanya, termasuk juga di atas kepentingan bangsa dan negara. Tentu dengan sering kali terjadinya peristiwa jatuhnya kabinet, kemudian akan menjadi pemicu utama daripada instabilitas jalannya pemerintahan, yang pada akhirnya tidak akan dapat menyelesaikan semua programnya, yaitu bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Inilah yang sebenarnya mendasari daripada UUDS 1950, dimana sistem pemerintahannya adalah mengutamakan tanggungjawab pemerintahan pada perdana menteri, beserta menteri-menterinya sebagai kesatuan kabinet kepada parlemen. Dengan demikian, ketentuan UUDS 1950 memiliki berbagai persamaan dengan negara-negara lain, yang tentunya juga menganut sistem pemerintahan parlementer. Bahkan jika kita telusuri kembali riwayat dari sejarah pembuatan UUDS 1950 itu sendiri, maka kita dapat mengutip pendapat dari Soepomo (1954;100) yang selanjutnya mengutip bunyi daripada ketentuan Pasal 95 Konstitusi Itali yang membandingkannya dengan ketentuan UUDS 1950, yang juga sama-sama menganut sistem pemerintahan parlementer, bunyinya yaitu The ministers are responsible collectively for actions of council of ministers and individually for those of their own ministers, serta Pasal 48 konstitusi Perancis yang berbunyi : The ministers shall be collectively responble to the National Assembly for general policy of cabinet and individually responble for their personel action. Dari kutipan pasal di atas tersebut, hanyalah bertujuan untuk membandingkan sistem pemerintahan parlementer antara Indonesia dengan dua negara leinnya, yang pada dasarnya sama-sama menganut sistem pemerintahan parlementer, dengan mengutamakan tanggungjawab kabinet kepada parlemen. Akibat dari adanya pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen yang dianut oleh UUDS 1950, telah menyebabkan instabilitas pemerintahan, yang kemudian ditandai dengan sering kalinya kabinet jatuh banging dikarenakan tidak mendapatkan dukungan suara, dalam menjalankan pemerintahan dari parlemen. Hal ini nampak dengan jelas, dari jumlah kabinet yang jatuh hanya dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1959. Pada waktu itu, parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu representasi daripada kedaulatan rakyat, yang benar-benar menunjukan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat, dengan melakukan kontrol atau pengawasan yang sangat efektif terhadap kabinet. Bahkan terlampau efektifnya parlemen dalam melaksanaan pengawasan terhadap kabinet, ternyata menjadi faktor utama yang menjadi penyebab daripada jatuhnya kabinet, karena mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen. Tampak kemudian dari 7 (tujuh) buah kabinet yang muncul dan silih berganti dalam periode 1950 sampai 1959. Pada waktu berlakunya Undang-Undang Sementara 1950, yang memang menganut sistem
I Gusti Ngurah Santika, SPd
92
pemerintahan parlementer - jadi selama lebih kurang 9 tahun Negara Kesatuan RI mempunyai 7 (tujuah) kabinet dengan usia sebagai berikut. 1. Kabinet Moh. Natsir, 6 September 1950-21 Maret 1951; 2. Kabinet Sukiman, 27April 1951 3 April 1952; 3. Kabinet Wilopo, 3 April 1952 30 Juli 1953; 4. Kabinet Ali, Wongso, Arifin, 30 Juli 1953 12 Agustus 1955; 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, 12 Agustus 1955 3 Maret 1956; 6. Kabinet Ali, Roem, Idham, 24 Maret 1956 14 Maret 1957; 7. Kabinet Djuanda, 9 April 1957 10 Juli 1959 (Djamali dalam Hutabarat dkk,1996;25). Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia pada waktu itu, memang mengalami krisis politik yang tidak berkesudahan dan menyusul berbagai kejadian lainnya, yang kemudian turut menambah dan menjadikan situasi semakin sulit untuk bisa diatasi oleh para pengambil kebijakan. Menurut Cangara (2009;4) bahwa krisis politik yang menyebabkan kabinet telah menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pemerintahan Indonesia, ditambah dengan mundurnya Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden 1956. Sebelumnya dapatlah dikatakan bahwa kecilnya peranan yang diberikan kepada seorang Presiden dan Wakil Presiden oleh UUDS 1950, padahal secara moral sebenarnya memiliki tanggungjawab begitu besar, seperti apa yang sebelumnya diharapkan oleh publik. Penulis berani mengatakan demikian disebabkan kepribadian dan peranannya yang dilakukan dalam perjuangan kemerdekaan (Kusnardi dan Sarigih,1986;140). Dapatlah diketahui bahwa sebelum mundurnya Hatta, Pada tahun 1952-1953 memperlihatkan secara umum melemahnya Hatta dan orang-orang lain yang serupa pandangannya, dan bersamaan itu terjadi kebangkitan Soekarno dan kelompok-kelompok nasional radikal di dalam partaipartai dan Angkatan Darat (Feit,2001;14). Sepeninggal Hatta pada tahun 1956 dari kursi Wakil Presiden dengan kemauan sendiri, sungguh pun banyak pihak-pihak yang mengharapkan ia terus juga memegang jabatan tersebut (Noer,1983;43). Keadaan ini tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi pemerintahan pada waktu itu, yang benar-benar tidak daya dalam menjalankan programnya. Karena sebelum menjalankan programnya terlebih dahulu dijatuhi mosi tidak percaya dari parlemen. Bahkan, alasan-alasan yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
93
digunakan untuk menjatuhkan kabinet, terkadang bukanlah suatu kesalahan yang bersifat fatal bahkan sifatnya relatif. Sehingga pada waktu itu faktor politislah yang kemudian mendominasi alasan parlemen untuk menjatuhkan kabinet. Dengan demikian, jelas sekali bahwa ketidak dewasaan dalam berpolitik merupakan faktor utama yang kemudian menyebabkan jatuh bangunnya kabinet. Ditambah dengan faktor lain lagi, yaitu kurang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan menyebabkan kesulitan untuk menemukan titik pemecahan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun pada waktu itu telah diusahakan untuk membangun sebuah kabinet yang solid, dengan jalan menjalin koalisi antar partai politik. Namun, dalam kenyataannya koalisi yang kemudian terbentuk, belumlah sepenuhnya dapat menjamin adanya stabilitas pemerintahan. Tidak lain, disebabkan dengan terlalu banyaknya partai politik yang ikut terlibat untuk selanjutnya berkompetisi dalam memperebutkan kursi yang ada di parlemen. Akhirnya menyebabkan tidak adanya satu partai politik mempu memegang kekuasaan mayoritas, untuk kemudian dapat menguasai kursi di parlemen. Alasan itulah nantinya menjadi penyebab kabinet yang dibentuk sebelumnya haruslah berdasarkan koalisi. Bahkan koalisi yang membentuk kabinet tersebut, tentunya terdiri dari berbagai macam kepentingan, tidaklah dapat berbuat banyak dalam usahanya untuk merealisasikan programnya, karena tidak dapat bertahan dalam menghadapi terpaan badai dari parlemen, berupa mosi tidak percaya. Terkait dengan jatuhnya kabinet yang hanya dalam waktu singkat, tidak lain disebabkan oleh mosi tidak percaya dari parlemen, yang pada dasarnya parlemen itu sendiri secara tidak langsung dibentuk oleh partai-partai politik, yang memperoleh kursi setelah mengikuti pemilihan umum. Dengan 7 buah kabinet yang jatuh dalam waktu singkat seperti disebutkan di atas, maka dengan demikian berarti usia tiap-tiap kabinet kurang lebih 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, Ismail Suny (1986;196) yang mengutip pidato Soekarno, yang dalam hal ini menyatakan ketidakpuasannya terhadap sistem multipartai.Tak seorangpun akan membantah bahwa suatu parlemen yang bercorak sedemikian itu akan sukar untuk memegangnya. Diharapkan bahwa pemilihan umum akan menyapu bersih sebagian besar dari pembagian yang tak pada tempatnya ini. Komentar presiden Soekarno mengenai sistem partai pada waktu itu: Akan tetapi, perkembangan demokrasi itu kadang-kadang menunjukan gejala-gejala, bahwa penggolongan ke dalam dua macam-macam partai itu bukan lagi penggolongan yang sehat, tetapi sudah mendekati sifat perpecah-pecahan. Bukan sifat defrensiasi yang rasionil, tetapi sudah versplinitering. Saya katakan perpecah-pecahan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
94
atau versplintering, oleh karena banyak dari partai-partai itu tidak menunjukan perbedaan-perbedaan besar mengenai dasar yang prinsipil. Tidak! Banyak dari partaipartai itu sangat boleh jadi hanya disebabkan oleh nafsu menonjolkan diri dari beberapa orang yang kurang mendapat perhatian masyarakat; oleh nafsu distintiedrang; oleh nafsu ingin berpengaruh. Oleh nafsu dia -mau-kursi, bukan demokrasi. Apa yang kita alami diwaktu-waktu belakangan ini ialah kadang-kadang bukan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, melainkan mempertahankan kepentingan golongan sendiri dan kepentingan diri sendiri, dan menjamin kepentingan kepentingan golongan sendiri dan kepentingan sendiri. Dengan mengutip pendapat Sanusi, Kantaprawira (1990;68) yang mencoba untuk mengambarkan bagaimana situasi dan kondisi perpolitikan pada waktu itu, ia menyatakan bahwa semua pemerintahan pada dasarnya adalah bersifat koalisi; karena itu pergeseran dukungan dari kelompok yang kecil sekali pun sudah cukup untuk menimbulkan perimbangan baru dalam parlemen. Krisis kabinet bisa terjadi setiap saat akibat soal kecilkecil yang dipermasalahkan beberapa orang wakil yang menimba keuntungan dari krisis tersebut. Masoed dan MacAndews (2006;55-56) menyatakan hal sama yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet dikarenakan kekurang mantapan kabinet sebagian berasal pula dari kenyataan bahwa ia merupakan sebuah koalisi yang bisa digoyahkan oleh pertikaianpertikaian yang terjadi antara partai-partai yang mendukungnya. Rupanya memang begitu, perangai mudah berkonflik masih melekat kuat, sehingga kabinet sering mengalami kesulitan mencapai consensus. Merpaung (2005;42) berpendapat bahwa dalam suasana pemerintahan parlementer, di mana partai-partai politik dan politisi dinilai tidak mampu mencegah pertarungan di antara mereka sehingga menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan demokrasi konstitusional, parlemen adalah merupakan representasi dari rakyat, terutama dalam sistem pemerintahan parlementer yang pada dasarnya meletakan seluruh pusat kekuasaan negara berada pada lembaga parlemen. Perlu diketahui bahwa terkait dengan persyaratan keanggotaan dalam parlemen, adalah biasanya dipilih melalui pemilihan umum. Namun, tentunya yang hanya bisa ikut menjadi kontestan untuk kemudian mengajukan calon, guna menduduki kursi di parlemen adalah partai politik. Dengan demikian, maka sistem kepartaian yang selanjutnya dipilih dalam suatu negara, tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang kemudian dijalankan. Jika saja sistem kepartaian yang sebelumnya digunakan adalah dua partai (dwi partai), yang disertai dengan sistem pemerintahan parlementer. Maka akan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
95
jelaslah kemudian pembagian tugas antara partai politik yang memenangkan suara rakyat dalam pemilu, yang berarti bertugas untuk memegang pemerintahan, dengan partai politik yang sebelumnya kalah dalam pemilihan umum yang bertugas sebagai oposisi/pengecam. Jika ditelusuri kembali riwayat sejarah dalam perjalanannya, yaitu pada periode berlakunya UUDS 1950, dapatlah kemudian dikatakan bahwa tidak ada partai politik mayoritas yang dapat memegang tanggungjawab jelas terutama dalam pemerintahan. Dikarenakan pada waktu itu, tidak adanya satu partai politik yang mampu memegang kursi lebih dari setengah di parlemen dengan tujuan untuk mengendalikan parlemen. Bahkan untuk menutupi kekurangan dari sistem kepartaian yang dianut pada waktu itu (multi partai) adalah dengan cara mengadakan koalisi antara partai-partai politik yang sebelumnya telah memperoleh kursi di parlemen. Namun, patutlah kemudian disayangkan bahwa koalisi tersebut, ternyata tidaklah mampu untuk menegakan stabilitas daripada pemerintahan. Dikarenakan partaipartai politik yang ada hanya mengkalkulasikan setiap kebijakan, yang kemungkinan akan diambil oleh pemerintah dengan keuntungan maupun kerugian, yang kemudian akan diperoleh partai politik yang bersangkutan jika nantinya kebijakan tersebut diambil. Faktorfaktor tersebutlah kemudian menyebabkan sikap yang terlihat apatis terhadap sistem pemerintahan parlementer. Bahkan yang kemudian menjadi kecaman utama pada waktu itu adalah partai politik yang merupakan posisi sentral kekuatan dari demokrasi parlementer, ternyata kecaman datang dari berbagai pihak, baik oleh rakyat maupun yang datang kemudian dari Seokarno. Dan pada bulan Oktober 1956 ini pula Presiden Sukarno mendesak agar partai-partai sebaiknya dikubur dan bahwa Demokrasi Liberal diganti dengan Demokrasi Terpimpin, demokrasi dengan kepemimpinan (Feith,2001;18). Tidak lain, dikarenakan konflik partai-partai yang sudah dianggap kebablasan dan mengancam persatuan. Karenanya, Bung Karno berpendapat partai-partai perlu dikuburkan (Alfian,2012;257). Bahkan implikasi utama dari konflik kepentingan antar partai politik tersebut, akhirnya berimbas secara tidak langsung pada lembaga parlemen, sehingga pada akhirnya berakibat pula terhadap jalannya roda pemerintahan. Mungkin apa yang menyebabkan hal tersebut di atas, akan dapat kemudian ditemukan jabawabannya dari apa yang selanjutnya dikemukakan oleh Rush dan Althoff (2008;73), yang menurut penulis pendapat mereka dapat memberikan sedikit gambaran tentang badan legislatif pada umumnya dan begitu juga keadaan untuk Indonesia pada khususnya, yaitu sebagai berikut. ada bukti yang menyatakan bahwa anggota badan legislatif mengalami proses sosialisasi segera sesudah pemilihan mereka; dan bahwa tingkah-laku legislatif
I Gusti Ngurah Santika, SPd
96
berikutnya sebagian ditentukan oleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap mereka seperti yang ada terdapat sebelum pemilihan, dan sebagian lagi oleh pengalamanpengalaman mereka semasa menjadi anggota badan legislatif, ditambah dengan reaksi-reaksi mereka terhadap lingkungan baru di badan legislatif. Dengan gambaran tersebut di atas, terkait dengan mudahnya konflik yang kemudian terjadi antara parlemen dengan pemerintah untuk kasus di Indonesia. Mungkin tidak lain dikarenakan oleh rendahnya pengetahuan yang sebelumnya mendasari sikap dan tingkah laku daripada anggota parlemen, yang sebenarnya masih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara. Yang pada akhirnya menimbulkan sikap acuh tak acuh anggota parlemen terhadap nasib rakyat. Menurut Mutis (2004;1) bahwa dalam hal itu masalah yang dihadapi ialah mengurangi kepentingan sempit serta tidak adil yang dipertahankan oleh sementara individu atau kelompok yang sudah saatnya harus diubah. Memang sebelumnya telah dipikirkan untuk selanjutnya akan mengadakan pemilihan umum, guna membentuk suatu pemerintahan solid seperti apa yang sebelumnya diidamidamkan. Bahkan dengan begitu pemerintahan diharapkan akan dapat berjalan efektif, karena tidak mungkin semua partai politik akan dapat memperoleh suara dalam pemilihan umum, untuk ikut duduk baik dalam parlemen maupun pemerintahan. Pemilihan umum pertama dilakukan, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian disusul pula pada bulan Desember 1955, yaitu dilaksanakannya pemilihan umum dengan dasar hukum UU No. 7 Tahun 1953 untuk memilih anggota-anggota Konstituante guna menetapkan UUD baru sebagai pengganti daripada UUDS 1950 yang bersifat sementara. Setelah terpilih kemudian dilanjutkan dengan pelantikan anggota Konstituante bertempat di Gedung Merdeka Bandung pada tanggal 10 November 1956 oleh Presiden Soekarno. Dengan dengan dibentuknya Konstituante, tentunya membawa harapan cukup besar bagi rakyat, yang nantinya akan dapat membentuk Undang-Undang Dasar tetap yang menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bahkan, dalam sidang pelantikannya di Bandung tersebut, Presiden soekarno telah pula berpesan kepada Konstuante, agar segera membuat undang-undang dasar dan tidak mengulur-ngulur waktu. Tentunya Konstituante diharapkan dapat membuat undang-undang dasar yang benar-benar untuk kepentingan rakyat. Menurut Asshiddiqie (2009;291) bahwa setelah itu dimulailah diadakan usaha untuk menyusun undang-undang dasar baru sama sekali dengan dibentuknya lembaga konstituante yang secara khusus ditugaskan untuk menyusun konstitusi baru.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
97
Terkait dengan hasil dari pemilihan umum pada waktu itu, dalam hal ini Karim (1983;9) menyatakan bahwa hasil pemilihan umum yang tidak melahirkan mayoritas suara pada salah satu kekuatan politik membuka peluang bagi adanya koalisi. Jika kita telusuri dari hasil pemilihan umum, maka pertama kali adalah partai Masyumi, yang menurut hasil Pemilihan Umum tahun 1955 merupakan partai paling besar sesudah PNI (Partai Nasional Indonesia, dan Partai Nahdatul Ulama yang merupakan partai paling besar nomor tiga sesudah Masyumi (Nasikun,2005;66). Dengan demikian, dapat dikatakanlah bahwa tidak ada satupun partai politik yang kemudian mampu memperoleh suara mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan, guna bersiap untuk menghadapi oposisi di parlemen. Namun, tidak dapat dicapainya mayoritas kursi di parlemen dari hasil pemilihan umum yang sebelumnya telah dilaksanakan, tenyata nasib sama juga dialami pada badan Konstituante yang sebenarnya bertugas untuk membentuk undang-undang baru yang bersifat tetap untuk kemudian menggantikan UUDS 1950. Dengan demikian, semenjak itu Konstituante telah menjadi medan perdebatan yang tidak berkesudahan, medan pertarungan bagi partai-partai dan pemimpin-pemimpin politik mengenai persoalan-persoalan prinsipil (Suny,1986;191). Menurut Maarif dalam Mahmud MD (2001;3) menyatakan bahwa perdebatan-perdebatan terhadap masalah-masalah pokok yang menjadi tugas badan itu (seperti masalah bentuk dan batas negara) berjalan cukup lancar, tetapi sekali tentang dasar negara disentuh, iklim politik dalam sidang menjadi sangat hangat. Feith (2001;16) menyatakan bahwa sebuah isu sentral muncul, apakah negara itu sebaiknya, seperti Masyumi meminta terutama didasarkan atas Islam; atau apakah, seperti PNI mengajukan pandangannya, dasar keagamaan itu sebaiknya yang telah ada dalam Pancasila itu, yang hanya menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apa yang kemudian dikatakan oleh Anshari (1986;86) bahwa the debates on political and philosophical principles inevitably provoked in the writing of any constitution, revealed the Constituent Assembly as a whole as divided into two : onne group wanting an Islamic basis for the state, the other demanding the acceptance of the Pancasila. Kesimpulan yang kemudian diperoleh dari perdebatan tersebut adalah sangatlah sulit untuk selanjutnya keluar dari medan pertarungan yang berkepanjangan tersebut. Di mana tidak lain dikarenakan penguasaan kursi oleh partai-partai politik yang berdebat dalam tubuh Konstituante ternyata tidak ada yang mampu untuk menguasai lebih dari 2/3 kursi. Tentunya dikarenakan banyaknya jumlah partai politik yang ikut terlibat untuk berkompetisi dalam pemilihan umum, yang tentunya membagi suara pemilih secara acak
I Gusti Ngurah Santika, SPd
98
kepada berbagai partai politik peserta pemilu pada waktu itu. Faktor itulah yang kemudian menyebabkan suhu politik menjadi semakin memanas, dikarenakan saling menonjolkan ideologi yang dianut dari masing-masing partai politik berbeda, untuk dijadikan dasar konstitusi baru yang akan disusun tersebut. Hal ini tentunya adalah sesuai dengan pendapat Noer (1983;3) yang menyatakan bahwa dalam tahun-tahun pertama kemerdekaan, apalagi dalam tahun 50 an, peranan partai sebegai saluran kehendak golongan yang memikul suatu suatu ideologi tampak menonjol ke depan. Ketika itu ideologi dapat dibedakan atas Nasionalisme, Islamisme, dan Komunisme (Kantaprawira,1990;80. Dengan demikian, yang menjadi masalah pada waktu itu adalah sistem multi partai yang dianut, pembentukan UUD baru yang selanjutnya akan menggantikan UUDS 1950 dan rendahnya stabilitas pemerintahan. Untuk menganalisis tentang terjadi pertentangan baik dalam tubuh Konstituante maupun parlemen, maka menurut Daniel S Lev yang kemudian dikutip oleh Safaat (2011;139) menyatakan bahwa sistem multi partai di Indonesia mengalami kekacauan seperti halnya sistem multipartai di negara lain. Di satu sisi terdapat partai politik kecil yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan. Namun, disisi lain terdapat partai besar yang kurang terlibat dalam pemerintahan. Permasalahan tersebut bertambah dengan berlakunya sistem parlementer tanpa adanya partai politik yang memiliki kekuasaan penuh terhadap parlemen dan pemerintahan. Inilah yang kemudian sebenarnya menjadi penyebab utama daripada pertikaian-pertikaian berkepanjangan, yang terjadi di tubuh parlemen. Sehingga pada gilirannya mengakibatkan jatuhnya stabilitas pemerintahan, yang juga berakibat jatuh bangunnya kabinet. Di sisi lain ada amanat besar, yang diharapkan oleh rakyat setelah adanya pemilihan umum, yaitu dibentuknya UUD baru yang menggantikan UUDS 1950 oleh sebuah badan yang bernama Konstituante. Namun, Konstituante bersama-sama dengan pemerintah yang bertugas membuat UUD baru yang menggantikan UUDS 1950 ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti apa yang kemudian diamanahkan oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan selama ini. Karena sidang-sidang Konstituante terus saja diwarnai oleh perdebatan-perdebatan yang tidak berujung pangkal, bahkan sudah mencapai titik klimaksnya. Tiga kali bersidang paripurna Konstituante selama lebih kurang dua setengah tahun tidak mampu menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia (Soehino,2007;38). Menurut sejarahnya, yang sebenarnya menjadi pangkal perselisihan dan perdebatan dalam Konstituante yang membuat pembahasan UUD baru berlarut-larut adalah Piagam Jakarta (Purwoko,2010;3). Perlu diingat bahwa masalah yang dihadapi pada masa sidang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
99
Konstituante berlangsung, di mana diperdebatkan mengenai dasar negara, yang akan berlaku seterusnya bagi negara Indonesia (Hadi,1994;37). Padahal dalam kenyataannya Konsituante sudah berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya, paling tidak untuk sebagian tugas-tugasnya tersebut, seperti berkenaan dengan hak asasi manusia, wilayah negara serta yang lainnya. Namun tetap saja ada satu masalah yang memang belum, bahkan tidak mungkin untuk dapat diselesaikan dengan waktu cepat, yaitu berkenaan dengan dasar negara yang akan berlaku untuk Indonesia. Dengan demikian, hal tersebutlah yang kemudian menjadi akar daripada permasalahan dalam perdebatan antara golongan nasionalis disatu pihak dengan golongan Islam dilain pihak. Pada waktu itu golongan nasionalis menginginkan Pancasila sebagai dasar negara dan Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Berkaitan dengan beberapa tugas daripada Konstituante yang sudah berhasil diselesaikan, berdasarkan keterangan yang diperoleh kemudian, paling tidak menurut Asshiddiqi dan Manan (2006;51) bahwa sebenarnya Konstituante telah berhasil merumuskan 90% UUD termasuk masalah HAM, hanya tinggal mengenai dasar negara. Perbedaan pendapat yang cukup tajam mengenai dasar negara di antara anggota-anggota konstituante itu sudah terang akan mendatangkan akibat-akibat negatif bagi masyarakat (Notosusanto dkk,1985;3). Kemudian timbul pula pendapat yang menghubungkan bahwa hal ini tidak lain dikarenakan sistem pemerintahan yang dianut pada waktu itu adalah sistem pemerintahan parlementer yang tidaklah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mengapa Indonesia pada waktu itu memilih model sistem pemerintahan parlementer, mungkin terkait dengan hal tersebut Wibawa dalam (Dwiyanto,2005;58) dapat memberikan alasannya bahwa model-model (sistem pemerintahan,penulis) yang pernah diterapkan di Indonesia merupakan hasil inspirasi dari dua hal, yaitu warisan kolonial dan respon terhadap konteks sosial politik yang berkembang. Dikarenakan, situasi dan kondisi politik dalam negeri yang kian lama semakin memperihatinkan, terutama yang disebabkan oleh jatuh bangunnya kabinet. Bahkan yang menjadi perhatian utama pada waktu itu adalah berkaitan dengan penyusunan UUD yang bersifat tetap oleh Konstituante. Namun, dari persidangan-persidangan Konstiuante yang sebelumnya berlangsung nampaknya belumlah dapat memenuhi semua keinginan rakyat, untuk segera dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang baru. Padahal sebelumnya menurut Fatmawati (2010;89) bahwa karena tak kunjung selesai maka, pada tanggal 22 April 1959 di depan DPR, Presiden berpidato agar Konstituante menetapkan UUD 1945 saja sebagai konstitusi. Kemudian untuk menanggapi pidato Soekarno sebelumnya tersebut, Konstituante selanjutnya mengadakan pemungutan suara
I Gusti Ngurah Santika, SPd
100
untuk mengambil keputusan, apakah akan menetapkan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar yang baru atau tidak. Namun patutlah kemudian disayangkan, karena sampai dengan tiga kali pemungutan suara yang diambil, ternyata belum juga memenuhi persyaratan kuorum untuk kemudian dinyatakan bahwa putusan yang diambil adalah saha, sebagaimana ditentukan dengan tegas dalam UUDS 1950. Dengan demikian, kedua golongan yang berhadapan tidak berhasil mencapai kompromi, padahal sudah sejak semula sudah bisa diduga tanpa suatu kompromi politik, konstituante akan gagal dalam mengambil keputusan. Mengapa?. Tidak lain disebabkan, baik partai-partai Islam (Masyumi, NU, PSII, Perti, PTII) maupun partai-partai pendukung dasar negara Pancasila, sama-sama tidak memenuhi syarat suara minimal untuk memenangkan sikapnya tentang UUD (Mahmud MD,2011;130). Hal ini dapat ketahui dalam UU yang berlandaskan UUDS 1950, yang pada dasarnya mensyaratkan bahwa untuk dapat dikatakan syahnya pengambilan keputusan dalam rangka membentuk sebuah UUD baru, hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya disetujui oleh minimal 2/3 dari anggota yang hadir dalam rapat. Padahal dalam kenyataannya partai Islam hanya mendapatkan 45% dan pendukung dasar Pancasila hanya 50% lebih sedikit. Lebih lengkapnya bahwa kedua golongan tersebut, tidak ada yang mampu untuk menguasai 2/3 suara, guna dapat memutuskan UUD baru. Menurut Seomantri (1992;60) bahwa dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sementara 1950 jelas, bahwa undang-undang dasar baru tidak akan mungkin ditetapkan, kecuali apabila ada kompromi di antara golongan-golongan (fraksi-fraksi) yang ada dalam konstituante. Dan kompromi selalu dimungkinkan terhadap hal-hal yang tidak mendasar. Akan tetapi terhadap hal-hal yang bersifat mendasar kompromi sukar dicapai. Hal ini terbukti pada waktu Konstituante RI akan mengambil sikap tentang dasar negara. Dengan demikian, keberadaan badan pembuat UUD yang baru ini, tidaklah mampu menghasilkan apapun dalam berbagai persidangannya selama ini. Dengan mengutip pernyataan Nasution dalam Anshari (1986;97) dapat kemudian ditegaskan bahwa in its two yers of existence the constituent Asembly produce nothing substantial. It became a forum of ideological debate. Oleh karena keadaan yang tidak menentukan seperti itu, Soekarno menganggap bahwa keadaan ini tentunya akan membahayakan negara proklamasi. Dikarenakan adanya pernyataan bahwa Masyumi tidak akan bersidang lagi, maka dengan tindakan sepihak dari Soekarno, yaitu dengan mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang salah satu keputusannya menetapkan untuk membubarkan badan Konstituante serta menetapkan UUD 1945 sebagai pengganti dari UUDS 1950. Di samping itu kita semua mengetahui bahwa juga dikalangan Angkatan Bersenjata menyetujui malahan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
101
menganjurkan ,,ide kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataan-kenyataan yang saja disebutkan tadi memperkuat keyakinan pemerintah, bahwa untuk mengatasi kesulitankesulitan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat semenjak kemerdekaan dan kedaulatan kita diakui pada akhir tahun 1949 dan untuk penyelesaian revolusi kita pada tingkatan sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bahan yang terbaik untuk dipergunakan kembali sebagai landasan (Kementerian Penerangan,tt;41). Dengan adanya tindakan kembali ke UUD 1945, disertai pula dengan pembubaran Konstituante adalah titik awal berakhirnya proses demokrasi di Indonesia, karena Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin untuk memenuhi kepentingan politik Soekarno dan tentara, yang watak kekuasaannya otoriter (Ilyas,2008;78). Namun, dalam hal ini Siagian (1983;43) berpendapat harus diakuilah bahwa untuk keadaan tertentu, seorang pemimpin yang demikian sangat diperlukan, akan tetapi sifat-sifatnya yang negatif mengalahkan sifat-sifat yang positif. Pendapat yang kemudian menyatakan bahwa Konstituante adalah gagal dalam menetapkan UUD 1945, merupakan suatu pernyataan yang tentu sepenuhnya tidak benar dan tidak dapat diterima. Dikarenakan hal ini dikarenakan permintaan Presiden Sekarno sebelumnya untuk kembali ke UUD 1945, sebenarnya telah mendapatkan jawaban dari Konstituante, yaitu dengan jalan voting (suara terbanyak) yang kemudian diambil sebanyak tiga kali, namun dalam kenyataannya tidak mencapai kuorum, seperti apa yang syaratkan oleh UUDS 1950. Maka, dengan demikian penulis berpendapat bahwa Konstituante dengan tegas menolak permintaan Soekarno untuk kembali ke UUD 1945, bukannya gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru dan ditambah lagi kemudian pada waktu itu merupakan masa reses Konstituante. Thoha (2011;140) menyatakan tentang hal ini bahwa Konstituante hasil pemilu pertama yang diserahi membentuk UUD tidak berhasil, karena dilanda konflik kepentingan dan keburu dibubarkan oleh Presiden Soekarno (kursif penulis). UUD Sementara 1950 hanya relatif singkat berlakunya. Sedangkan UUD 1945 mengalami dua kali dari 1945 sampai sekarang. Setelah Presiden melakukan tindakan sebelumnya untuk memberlakukan UUD 1945 dengan cara mencabut UUDS 1950 yang disertai pembubaran Konstituante secara sepihak, bahkan Konstituante sendiri setelah dibubarkan ternyata tidak diperkenankan untuk kembali melakukan sidang. Dari berbagai tindakan yang sebelumnya diambil oleh Soekarno tersebut, tidaklah mungkin dapat diterima sepenuh terutama oleh sebagaian orang yang dulunya pernah dekat dengan beliau. Kecaman kemudian datang dari berbagai pihak terutama setelah dikeluarkannya Dekrit
I Gusti Ngurah Santika, SPd
102
Presiden, yaitu dari Moh. Hatta dan Parwoto Mangkusasmito, yang kemudian menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Soekarno sebagai tindakan kudeta terhadap negara Indonesia. Alasan yang selanjutnya dinyatakan oleh mantan Wapres Mohammad Hatta, misalnya terkait Dekrit Presiden tersebut adalah inkonstitusional, karena Presiden tidaklah berwenang membubarkan Konstituante. Begitu juga Presiden secara riil tidak berhak menyatakan pencabutan terhadap UUD yang berlaku dan memberlakukan UUD baru, karena kewenangan untuk itu hanya dimiliki oleh Konstituante seperti yang diatur di dalam UUDS 1950 yang berlaku ketika itu (Mahmud MD,2001;58). Meski cukup banyak kritik dan komentar yang muncul sehubungan dengan diberlakukannya Dekrit 5 Juli 1959 itu, dalam praktiknya dekrit ini pada akhirnya diterima dan dianggap final sebagai dasar berlakunya UUD 1945, dan menjadi titik tolak munculnya demokrasi baru yang disebut demokrasi terpimpin (Cangara,2009;5). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model perubahan konstitusi yang dilakukan melalui Dekrit Presiden, merupakan perubahan konstitusi melalui prosedur yang kemudian disebut dengan Verfassung-wandlung. Yakni perubahan konstitusi yang tidak dilakukan berdasarkan legal formal, seperti apa yang ditentukan dalam konstitusi itu sendiri, melainkan melalui jalur istimewa seperti revolusi, kudeta (coupdetat), dan konvensi (Syahuri,2004;48). Namun demikian, ternyata banyak pula yang kemudian mendukung keputusan presiden dengan alasan Staatnoodrecht dalam arti subyektif adalah hak negara dalam keadaan darurat untuk bertindak dengan dapat menyimpang dari undang-undang dasar (Suardana,2011;19). Pendapat yang sama ternyata juga dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikro yang ketika itu merupakan Ketua Mahkamah Agung, yang dalam pernyataannya menegaskan, bahwa Dekrit itu sah berlakunya karena jika negara dalam keadaan bahaya maka presiden dapat mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkannya, termasuk tindakan yang ada di luar ketentuan yang bertentangan dengan UUD. Dalil yang dipergunakan untuk memperkuat argumen ini adalah salus populi supreme lex, keselamatan rakyat dan negara adalah hukum yang tertinggi. Bahkan (keselamatan) lebih tinggi daripada UUD (Mahmud MD,2009;127). Bukti diterimanya dekrit tersebut dapat dilihat kembali, terutama dengan adanya penerimaan wakil rakyat di DPR. Pada tanggal 22 Juli 1959 DPR mengadakan sidang pleno dan dengan suara bulat DPR bersedia bekerja sama terus dengan Presiden dalam rangka UUD 1945 (Isra,2010;131). Apabila pada permulaan masih ada keragu-raguan tentang sah tidaknya keputusan itu (dekrit), keragu-raguan itu tidak beralasan lagi sejak DPR yang dipilih oleh rakyat dan boleh dianggap membawakan suara rakyat dalam sidangnya pada tanggal 22 Juli 1959 (Tutik,2008;149). Sebelumnya adanya dekrit tersebut dapatlah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
103
diketahui bahwa menurut keterangan dalam keputusan Dewan Menteri tertanggal 19 Februari 1959, maka sekembalinya ke UUD tahun 1945 itu adalah guna melaksanakan demokrasi terpimpin (di Indonesia) yang berdasarkan suatu ekonomi terpimpin (Utrecht,1986; 48). 4. 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 (Orde Lama) Setelah ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno (Elson,2009;324) maka sebagai konsekuensinya seluruh aspek ketatanegaraan mesti segera disesuaikan dengan ketentuan UUD 1945 yang telah berlaku kembali. Untuk itu, dibentuklah alat-alat perlengkapan negara, seperti MPRS dan DPAS sesuai dengan bunyi dari Dekrit Presiden tersebut. Hal mana adalah sesuai dengan bunyi daripada Dekrit Presiden tersebut, yang salah satu dari keputusannya itu menyatakan akan membentuk lembaga MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan berkaitan dengan kedudukan kabinet dalam UUD 1945, Kusnardi dan Sarigih (1986;141) menyatakan bahwa dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka pada tanggal 10 Juli 1959 terbentuklah kabinet pertama sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu kabinet yang menteri-menterinya adalah sebagai pembantu Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Semua hal tersebut dilakukan dengan membentuk alat-alat perlengkapan lembaga negara semata-mata tidak lain untuk menyesuaikan dengan UUD 1945. Walaupun alat-alat perlengkapan negara tersebut di atas masih bersifat sementara, hal itu berarti telah dilaksanakannya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak seperti yang terjadi pada periode pertama (Soemantri,1989;66). Kiranya kita mengingatkan kembali kejadian bersejarah pada tanggal 10 November 1960, bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan, ketika di gedung Majelis Permuyawaratan Rakyat di Bandung dilakukan pembukaan sidang pertama dari Majelis Permusyawaran Rakyat Sementara (MPRS), hingga menjadi lengkaplah lembaga-lembaga ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar (MPRS dan Departemen Penerangan,1960;9). Mengapa dalam Dekrit Presiden tersebut tidak dinyatakan akan membentuk DPR, melainkan hanya menyebutkan dua lembaga negara yang nantinya akan dibentuk setelah ditetapkannya UUD 1945, yaitu MPRS dan DPAS? Hal ini dapat diketahui dari sistem ketatanegaran yang berlaku sebelumnya dalam UUDS, yang di dalamnya ternyata tidaklah mengenal lembaga negara yang bernama MPR dan DPA, sedangkan untuk DPR ternyata UUDS 1950 mengakui keberadaannya secara konstitusional. Bahkan pada periode sebelum berlakunya kembali UUD 1945 dalam kenyataannya telah pula dilangsungkannya sebuah pemilihan umum. Pada waktu itu, selain diadakannya pemilihan umum untuk memilih
I Gusti Ngurah Santika, SPd
104
anggota Konstituante, ternyata juga diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Joeniarto (dalam Mahmud MD,2011;130) bahwa pada tahun 1953 pemerintah bersama DPR menyetujui UU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu UU No. 7 Tahun 1953. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955, dengan dua kali pemungutan suara, yaitu untuk anggota DPR dilakukan pada bulan September dan untuk anggota konstituante dilakukan pada bulan Desember 1955. Dan ternyata setelah jatuhnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ternyata lembaga DPR bersedia bekerja di bawah UUD 1945, sehingga Presiden hanya perlu membentuk MPRS dan DPAS (S=Sementara) yang memang setelah ditetapkannya UUD 1945 kembali belumlah terbentuk. Kenapa nama lembaga negara tersebut bersifat sementara? Tidak lain dikarenakan pada waktu itu belumlah dapat diadakan sebuah pemilihan umum untuk kemudian memilih anggota-anggota yang selanjutnya akan duduk di dalam lembaga-lembaga negara tersebut, yang nantinya akan mewakili rakyat, terutama untuk mengisi keanggotaan dalam lembaga MPR. Untuk itu, idealnya sebagai wakil rakyat, maka anggota MPR merupakan pilihan daripada rakyat yang berdaulat dalam pemilu demokratis. Berkenaan dengan sistem politik yang berlangsung pada waktu Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, ternyata partai politik yang merupakan salah satu pilar demokrasi tidaklah mendapatkan angin yang segar. Sementara itu, jika ditelisik kembali, dari sistem politik yang berlaku terutama berkaitan dengan kedudukan partai politik, maka hanya PKI sajalah yang kemudian mendapatkan kebebasan dalam melakukan kegiatan politiknya. Sedangkan untuk partai-partai politik lainnya yang pada waktu itu tidak sepaham dengan keinginan pemerintah akan mendapatkan tekanan, apalagi kemudian terang-terangan berani untuk tidak mendukung semua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, sesuailah semboyan demokrasi pemimpin yang seringkali dilontarkan dari mulut Soekarno, yaitu dengan membentuk sebuah kepemimpinan yang kuat dengan menyingkirkan jauh-jauh partai politik dari gelanggang politik. Bahkan lebih lanjut menurutnya bahwa partai politiklah selama ini yang merupakan segala akar daripada permasalahan di dalam sistem pemerintahan. Munculnya demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi multipartai dan sistem pemerintahan parlementer yang dijalankan sebelumnya. Banyak partai politik dipandang merupakan salah satu masalah yang menyebabkan tidak stabilnya pemerintahan dan munculnya perpecahan bangsa (Safa,at,2011;138). Sejalan dengan pendapat tersebut, Sanit (2011;12) dalam hal ini menyatakan bahwa semenjak lumpuhnya demokrasi berdasarkan kepada partai dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
105
munculnya Soekarno dengan sistem politik demokrasi tertpimpin, pandangan masyarakat terhadap partai menjadi kurang baik. Di samping peranan partai yang sudah merosot, tumbuhlah anggapan bahwa partai adalah penyebab ketidakstabilan politik sehingga pantaslah disalahkan atas kegagalan eksperimentasi demokrasi konstitusional sebelumnya. Sebenarnya pernyataan oleh Presiden tersebut sudah lama diucapkan, namun ketika itu belumlah mendapat kesempatan untuk dilaksanakan. Kemudian keinginan terbesar Presiden Soekarno agar partai-partai politik itu dikubur saja, akhirnya mendapat bentuknya yang konkret, yaitu dengan dikeluarkannya sebuah Penpres Nomor 7 Tahun 1959, yang pada intinya menyederhanakan jumlah partai politik. Yang sebelumnya dalam Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tidaklah ditentukan persyaratan yang jelas tentang syaratsyarat untuk pendirian partai politik. Kemudian dengan lahirnya Penpres No 7 Tahun 1959 diadakan penyesuaian terhadap partai politik oleh pemerintah, agar selanjutnya diakui keberadaannya. ternyata setelah diadakan seleksi berdasarkan peraturan tersebut, maka yang dapat lolos hanya 10 partai politik saja. Dengan demikian, keluarnya peraturan tersebut adalah sebagai upaya untuk menutupi kedok dari Soekarno saja, dengan tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengurangi pengaruh partai politik terhadap cita-cita Soekarno itu sendiri, untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai pusat daripada kekuasaan negara. Sejak Soekarno menempatkan dirinya sebagai figur pusat seluruh jaringan kekuasaan, partai-partai politik kehilangan dunianya. Keadaan ini sudah mulai kita saksikan sejak jatuhnya kabinet parlementer terakhir (kabinet Ali II), pada bulan Maret 1957. Hal ini juga menyatakan bahwa demokrasi parlementer mendekati kejatuhannya (Karim,1983;XII). Bahkan, terkait dengan kedudukan partai politik, menurut Mac Andrews dan Amal (2003;14) bahwa, pada periode Demokrasi Terpimpin (1957-1965), sangat menyadari pentingnya pemerintahan pusat yang kuatPartai-partai politik yang sangat dominan pada periode sebelumnya dicabut dari akar pendukungnya melalui laranganlarangan. Hal ini dengan sendirinya membatasi kemampuan mereka dalam memobilisasi dukungan. Konfigurasi pada era Soekarno ini ditandai dengan tarik menarik antara kekuatan yang ada, antara tiga kekuatan politik, yaitu Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI dengan Soekarno yang berada paling atas. Ketiga kekuatan ini pada dasarnya adalah saling memanfaatkan satu sama lainnya. Soekarno memerlukan PKI untuk menghadapi Angkatan Darat, sedangkan Angkatan Darat memerlukan Soekarno untuk mendapatkan legitimasi bagi keterlibatannya dalam politik (Mahmud,2011). Terakhir adalah PKI memerlukan perlindungan dari Soekarno untuk mendapatkan perlindungan dari Presiden untuk melawan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
106
angkatan darat. Namun dikarenakan kurangnya kekuatan pendukung yang terorganisasi, maka Soekarno selalu menghadapi bahaya lebih bergantung kepada tentara daripada sebaliknya. Maka ia terpaksa selalu mengimbangi kekuatan kelompok-kelompok lain (Feith,2001;43). Setelah mengambil keputusan dengan mengembalikan kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam kenyataannya yang terjadi bukannya bertambah baik, tetapi malahan terpusatnya semua kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Bahkan, dengan terpusatnya semua kakuasaan pada diri pribadi presiden tersebut, nyaris menjadikannya sebagai presiden yang benar-benar lepas dari kendali, bahkan kemudian menjadi diktaktor/otoriter. Berbagai tindakan Soekarno dalam bidang ketatanegaraan yang tidak lazim, bahkan sangat menyimpang dari ketentuan UUD 1945, yang pada dasarnya merupakan pedoman utama yang seharusnya diikuti. Pelanggaran nyata yang dilakukan oleh Soekarno terhadap UUD 1945, seperti adanya rangkap jabatan antara pimpinan lembaga negara tertentu, misalnya Ketua DPRS diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga tugas yang seharusnya terpisah, kemudian terlihat seolah-olah merupakan bagian dari eksekutif, hal mana dikarenakan jabatan menteri itu sendiri memang pada dasarnya adalah sebagai pembantu Presiden. Selain Ketua DPR yang merangkap jabatan, juga dalam hal ini adalah Ketua MA diberikan kedudukan sebagai menteri yang seharusnya terpisah dari semua kekuasaan manapun, terutama dari lembaga eksekutif. Bahkan, tindakan yang dipandang sangat menyimpang dari konstitusi adalah dengan adanya pembubaran terhadap badan legislatif (DPR) hanya dengan sebuah Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, karena masalah anggaran yang tidak disetujui oleh DPR. Keterangan yang sama juga diberikan oleh Lev dalam Amal (2012;161) yang menyatakan bahwa pada bulan Maret 1960 Soekarno membubarkan parlemen atas dasar isu anggaran. Parlemen Gotong Royong yang baru ditunjuk oleh Soekarno tetap mempertahankan representasi partai, bersama-sama dengan golongan fungsional. Namun, baik partai maupun parlemen, keduanya kehilangan otoritas dan kebebasannya. Menurut Budiardjo (2008;334) bahwa DPR Peralihan ini dibubarkan dengan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 justru karena timbul perselisihan antara pemerintah dengan DPR Peralihan ini mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di mana dari 44 Miliar rupiah yang diajukan pemerintah hanya disetujui sekitar 36 sampai 38 miliar rupiah saja. Peristiwa seperti tersebut di atas, pada dasarnya merupakan bentuk tindakan Presiden yang bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian ditambah dengan tindakan lainnya yang kemudian dapat digolongkan bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, adalah adanya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
107
pengangkatan anggota DPRGR dengan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tanpa melalui pemilihan umum. Bahkan, adanya peristiwa yang bisa dikatakan sangat mencolok, terkait dengan adanya pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dengan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963. Yang tentunya jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Presiden memegang jabatan selama lima tahun walaupun setelah itu dapat dipilih kembali tanpa adanya batasan yang jelas. Untuk mengetahui dengan jelas adanya peristiwa tersebut perlu dipahami latar belakang keluarnya Tap MPRS No. III/1963 tersebut. Menurut Silaloho (1999;10) bahwa tahun 1963, setelah Irian Barat berhasil direbut, bung Karno kembali mengajak melaksanakan pemilu, tetapi hampir seluruh partai pada waktu itu tidak menyetujui, kecuali PKI. Malah yang terjadi, beberapa partai politik meminta supaya Bung Karno diangkat sebagai Presiden seumur hidup, untuk mencegah agar Presiden tidak dari PKI. Selain pelanggaran terhadap UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, ternyata juga ada ketentuan yang pada dasarnya membenarkan tindakan Presiden untuk campur tangan dalam bidang peradilan, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964. Yang mana undang-undang tersebut jelaslah sangat bertentangan dengan bunyi Penjelasan dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, yang terlepas dari campur tangan kekuasaan eksekutif. Kemudian campur tangan Presiden dalam bidang legislatif, yaitu dengan keluarnya UU No. 14 Tahun 1960. Yang dalam hal ini, jika DPR tidak mufakat dalam mengambil sebuah keputusan, maka presiden dibenarkan untuk ikut campur tangan dalam pengambilan keputusan tersebut, walaupun tetap dengan memperhatikan pendapatpendapat yang dikemukakan di DPR. Berbagai tindakan yang dilakukan itu semua, telah menyebabkan sebagian orang menilai tingkah laku politik Soekarno sebagai bukan saja menyeleweng dari Demokrasi Pancasila, tetapi juga mengandung ciri-ciri otoriter (Masoed dan Andrews,2006;252). Seperti apa yang dinyatakan di atas, bahwa dalam situasi dan kondisi sedang berlangsungnya demokrasi terpimpin pada waktu itu adalah dengan menempatkan pribadi Soekarno sebagai pusat daripada pengambilan keputusan negara. Hal tersebut tidak lain dikarenakan oleh Richklefs (2007;387) bahwa demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun prakarsa untuk pelaksanaannya diambilnya bersama-sama dengan pimpinan angkatan bersenjata. Dari paparan yang sebelumnya telah disampaikan tersebut di atas, berkaitan dengan tipe kepemimpinan yang mungkin menjadi gaya Soekarno dalam menjalankan pemerintahan adalah kharismatik di samping juga di dasari
I Gusti Ngurah Santika, SPd
108
dengan kepemimpinan yang bersifat legal (sah secara hukum). Sedangkan biasanya dikenal tiga model kepemimpinan seperti apa yang kemudian diajukan oleh Weber (2006;94) yaitu tradisional, legal, atau kharismatik. Lebih lanjut menurutnya dalam ketiga tipe kepemimpinan adalah yang paling jelas, dalam mencari legitimasi kepatuhan ini, orang bertemu dengan ketiga tipe murni tersebut: tradisional, kharismatik dan legal (Weber,2006;94). Bahkan, tipe kepemimpinan Soekarno yang kharimatis serta rasional legal tersebut bisa muncul disemua tempat dan dalam setiap zaman sejarah. Ketiga tipe kewenangan tersebut bisa saling berkombinasi antara satu sama lain (Damsar,2010;70). Dengan tipe kepemimpinan yang sebelumnya dimiliki oleh Soekarno, terutama jika dicermati dari segi kharisma tersebut, dalam kenyataannya hanya menonjolkan kebanyakan sisi negatif. Padahal sebelumnya ia dengan tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang kemudian akan dijalankan adalah sebuah demokrasi walaupun terpimpin. Dalam konstruksi ini unsur demokrasi tetap mempunyai peranan yang penting sekali, tetapi bukan demokrasi liberal namun demokrasi terpimpin yang tidak lagi didasarkan atas paham trias politika (Adisubrata,2003;57). Bahkan, jika saja dianalisis kembali terkait dengan tipe kepemimpinan, seperti apa yang disebutkan oleh Gerungan (2002;40-41), dalam kenyataannya terdiri dari kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokrasi, dan dengan cara laissez-faire, maka dapatlah kemudian dikatakan bahwa kepemimpinan Soekarno tergolong tipe kepemimpinan otoriter, yang ternyata juga didasari oleh tipe kepemimpinan kharismatik dan legal rasional menurut Max Weber. Tindakan-tindakan Soekarno dalam menjalankan pemerintahan pada dasarnya jelas-jelas sangat bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga pada periode ini meskipun secara legal konstitusional UUD 1945 sebenarnya sudah berlaku, namun secara sosiologis belumlah kemudian dapat diimplementasikan secara murni dan konsekuen dalam kehidupan kenegaraan. Dengan demikian, sampai diberlakukan kembali pada tanggal 5 Juli 1959, UUD 1945 itu sebenarnya memang belum sempat diterapkan dengan sebaik-baiknya (Asshiddiqie, 2005;83). Berdasarkan, pemaparan di atas maka dapatlah disebutkan hal-hal apa saja yang sebelumnya dilakukan oleh Soekarno, yang kemudian tergolong sebagai perbuatan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Rindjin (2009;307) penyelewengan sebagaimana dimaksudkan di atas, yaitu. 1. Lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara bersifat sementara.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
109
2. Kekacauan pembagian kekuasaan di antara lembaga tinggi negara (yudikatif, eksekutif dan legislatif), seperti ketua DPR GR menjadi menteri, ketua Mahkamah Agung menjadi menteri, dsb. 3. Tap MPRS tentang pemimpin besar revolusi. 4. Tap MPRS tentang Presiden seumur hidup. 5. Adanya Penetapan Presiden (Penpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, bahkan dikatakan bersumber dari hukum revolusi. 6. Terjadinya G.30. S PKI (30/09/1965). 7. Gagasan Demokrasi Terpimpin sebagai reaksi terhadap Demokrasi Liberal yang menyebabkan instabilitas politik dan pemerintahan dalam praktiknya menjurus ke arah kekuasaan yang otoriter sehingga menyumbat saluran aspirasi dan ABS. Selain apa yang telah dikemukakan oleh Rindjin, terkait dengan penyimpanganpenyimpangan konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang telah dilakukan oleh Soekarno/Orde Lama pada waktu itu. Kansil dan Christine (2011;68) dalam hal ini juga memaparkan penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya dilakukan oleh Orde Lama, di mana tentunya ada beberapa kemiripan dengan apa yang sebelumnya telah dinyatakan pula oleh Rindjin. Penyimpangan sebagaimana dimaksudkan tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. MPR, DPR, DPA, dan BPK belum terbentuk berdasarkan UUD 1945, yang ada ialah MPRS, DPR-GR, dan DPAS. 2. Presiden telah mengeluarkan produk-produk legislasi yang mestinya berbentuk undang-undang (artinya dengan persetujuan DPR) namun dalam bentuk Penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. 3. Pangangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS, sedangkan UUD 1945 menetapkan masa jabatan Presiden 5 Tahun. 4. Hak buget tidak berjalan, artinya pemerintah tidak mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
110
5. Pada tahun 1960 Presiden membubarkan DPR, karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah. Lebih lanjut, terkait dengan hal tersebut di atas, maka Tutik (2008;152-153) memberikan pernyataan tentang adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 pada masa pemerintahan Soekarno. Penyimpangan sebagaimana dimaksudkan, yaitu. 1. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, di mana Presiden membentuk MPRS dan DPAS dengan Penpres Nomor 2 Tahun 1955 yang bertentangan sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dalam UUD 1945; 2. Penentuan masa jabatan Presiden seumur hidup, hal ini tentunya bertentangan dengan pasal UUD yang menyebutkan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali; 3. Berdirinya Partai Komunis Indonesia yang berhaluan atheism, hal ini bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang pada sila pertama menyebutkan Ketuhanan Maha Esa artinya bahwa bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan. 4. Adanya kudeta dari PKI dengan Gerakan 30 Septembernya (G 30 S/PKI) yang jelas-jelas akan membentuk Negara Komunis di Indonesia, hal ini merupakan penyimpangan terbesar terhadap pelaksanaan UUD 1945. Berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi, terutama dengan UUD 1945. Bahkan semua peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden ternyata hanya berdasarkan apa yang sebelumnya menjadi ucapannya. Menurut Noer (1983;75) hal tersebut terasa sekali dalam zaman Demokrasi Terpimpin. Tiap pidato Presiden Soekarno ketika itu seakan sudah menjadi sumber hukum. Kekuatan hukumnya (seperti dalam hal Manifesto Politik tahun 1960) baru diresmikan kemudian (yaitu tahun 1961 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) tetapi apa yang tertera di dalamnya sudah harus berjalan sebelum kekuatan hukumnya dinyatakan secara resmi. Malah penetapan Presiden dipandang sekurang-kurangnya sama dengan undang-undang kalau pun lebih tinggi. Masa itu memang luar biasa, bukan dalam arti bahwa masa itu perlu dikagumi melainkan dalam arti bahwa banyak hal-hal yang berjalan di luar kebiasaan.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
111
Dalam perjalanannya pada era Soekarno banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan UUD 1945. Pelanggaraan yang kemudian menjadi paling penting adalah membiarkan berkembang PKI sebagai sebuah organisasi politik yang dalam kenyataannya bahkan mendapatkan perlakuan yang bersifat istimewa dari Presiden, selanjutnya mengukuhkannya dengan membentuk sebuah wadah yang kemudian bernama NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Ricklefs (2007;406) berpendapat bahwa tampaknya doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (untuk nasionalisme), NU (untuk agama), dan PKI (untuk komunisme) akan bersama-sama berperan dalam pemerintahan disegala tingkatan, sehingga menghasilkan suatu sistem yang antara lain, akan didasarkan pada koalisi kekuatan-kekuatan politik yang berpusat di Jawa. Bukti lain tentang adanya keseriusan dukungan pemerintah terhadap PKI, yaitu dengan adanya approach negaranegara luar komunis yang sukses diterima sebagai sahabat akrab (poros-Jakartaphonompeach-peking) dan masa komunisasi (Djahiri,1978;25). Dengan demikian, terlihatlah bentuk daripada keseriusan pemerintah dalam mendukung tindakan PKI. Bahkan PKI pada waktu itu merupakan suatu organisasi yang memiliki dukungan luas dari rakyat, terutama dari kaum lapisan bawah seperti petani dan buruh. Mungkin penyebab dari luasnya dukungan rakyat terhadap PKI dapat diperoleh dari keterangan Satropoetro (1988;18) yang menyatakan bahwa dalam tubuh organisasi Front Nasional dahulu misalnya, terdapat suatu bagian yang disebut Indo Prop (Indoktrinasi dan Propaganda). Bahkan pada waktu itu, dibentuk pula Dewan Nasional oleh Soekarno yang sebelumnya telah mendapat banyak tantangan, termasuk dari Hatta sendiri. Karena pada dasarnya pembentukan Dewan Nasional tersebut tidaklah ada landasan hukumnya, serta jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Namun, akhirnya pembentukan Dewan Nasional dapat dilaksanakan. Badan ini adalah sebuah lembaga negara seperti Dewan Pertimbangan Agung, dengan anggota wakil-wakil golongan fungsional (Hutabarat dkk,1996;26). Lebih lanjut, berkaitan dengan kedudukan Partai Komunis yang semakin lama menjadi semakin kokoh, dikarenakan intensifnya propagandapropaganda yang sebelumnya dilancarkan. Partai Komunis menjadi semakin kokoh dan kuat karena memiliki banyak dukungan dari rakyat terutama dari lapisan bawah. Bahkan, dalam sejarahnya PKI ternyata sempat untuk mengusulkan agar para petani dan buruh diberikan senjata (dipersenjatai) dan kemudiam diangkat sebagai Angkatan Kelima, yaitu selain AD, AL, AU dan Polri. Sebenarnya semenjak pencanangan Demokrasi terpimpin dan peluncuran bahan indoktrinasi yang terkenal dengan singkatan Manipol Usdek (Manifesto Politik dan UUD
I Gusti Ngurah Santika, SPd
112
1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Kepribadian Indonesia) oleh Soekarno pada pidato kenegaraan 17 Agustus 1959, yang disusul dengan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) yang dipaksakan untuk diterapkan pada seluruh serta setiap kegiatan bernegara dan bermasyarakat, maka Partai Komunis Indoonesia yang sudah lama mengintai-ngintai segera memanfaatkan kesempatan emas ini (Ismail,2002;X). Ternyata, PKI dengan tegas telah berani mengkhianati semua kepercayaan yang sebelumnya diberikan Presiden Soekarno. Bahkan disertai dengan kehendaknya untuk menggantikan dasar negara Pancasila, yang kemudian ditentang keras oleh Angkatan Darat. Berlanjutnya pertikaian tersebut akhirnya sampai memakan banyak korban, terutama dari pihak AD yang kehilangan pejuang-pejuang sejati bahkan rela mati daripada mengorbankan bangsa. Namun, pertikaian antara PKI dan AD tersebut kemudian diakhiri dengan kekalahan telak dipihak PKI dan munculnya Angkatan Darat sebagai pemenang. Dengan terjadinya kekacauan politik, keamanan dan ekonomi terjadi setelah peristiwa G. 30. S/PKI. Bahkan menurut Prakoso (1986;10) bahwa peristiwa-peristiwa tersebut di atas pada dasarnya merupakan perebutan kekuasaan pemerintah yang sah ke dalam kekuasaannya. Ghaffur (2011;91) berpendapat bahwa setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI, Presiden Soekarno dihadapkan pada situasi politik yang semakin sulit. Presiden menerima tuntutan yang terkenal dengan sebutan tri tuntutan rakyat (Tritura). Isi dari tuntutan tersebut adalah Presiden diminta untuk membubarkan PKI, membersihkan kabinet dari unsur PKI, dan menurunkan harga pokok kebutuhan hidup. Dengan datangnya berbagai desakan dari seluruh sudut, maka pemerintah ketika itu benar-benar tidak mampu untuk menahan gelombang tuntutan dipelopori oleh para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi, seperti KAMI, KAMMI, KAPI dan organisasi kepemudaan yang lain (Tutik,2008;153). Sedangkan dilain pihak ternyata pada waktu itu, Presiden Soekarno mengalami gangguan kesehatan, maka segera dikeluarkanlah Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu berupa penyerahan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto yang masih penuh misteri dan kontroversial (Fadjar,2008;31). Namun, menurut Soehino (2010;41) bahwa kekuatan berlakunya Surat Perintah 11 Maret 1966 tersebut terletak pada penerimaan, pembenaran, serta dukungan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Ternyata dalam perkembangannya ke depan, Surat Perintah 11 Maret 1966 tersebut dibenarkan serta diterima secara aklamasi dan secara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. Maka, berakhirlah kekuasaan Soekarno, yang kemudian dilanjutkan dengan datangnya pemerintahan Soeharto. Semua itu terjadi tidak lain dikarenakan bahwa keseluruhan Pidato Presiden/Mandataris Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 22 Juni 1966
I Gusti Ngurah Santika, SPd
113
yang berjudul Nawaksara dan Surat Presiden Mandataris Majelis Pemusyawaratan Sementara Rakyat Sementara tertanggal 10 Januari No. 01/Pres/1967 tentang Pelengkap Nawaksara, tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya, anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada khususnya, karena tidak memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden mengenai Pemberontakan kontra revolusi G-30-S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak (Notosusanto,1984;16). Dengan demikian, kesimpulan yang kemudian diambil dalam demokrasi terpimpin, dalam menjalankan pemerintahannya ternyata bukanlah menggunakan prinsip-prinsip demokrasi untuk mencapai kehidupan demokratis. Menurut Taniredja dkk (2011;17) bahwa untuk mengajarkan demokrasi itu harus dalam suasana yang demokratis dan mendukung kehidupan yang demokratis (teching in and for democracy). Istilah Demokrasi terpimpin ternyata telah banyak benar menimbulkan kesalah pahaman tentang wujud demokrasi dalam negara kita, antara lain menggeser pengertian kedaulatan rakyat ke arah pengertian kedaulatan negara atau ke arah pengertian kedaulatan pemerintah beserta alat-alatnya, sampai-sampai terdengar tuduhantuduhan ke arah kediktaktoran (Karim,1990;13). Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 melahirkan Demokrasi Terpimpin, sistem demokrasi yang kekurangannya hanya satu, yaitu absennya demokrasi itu sendiri (Urbaningrum,2004;26). 5. Periode 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1988 (Orde Baru) Pada awal berdirinya, rezim Orde Baru mendeklarasikan diri sebagai kritik atas rezim Orde Lama. Kritik yang paling utama adalah bahwa Orde Lama telah gagal membangun dukungan politik masyarakat, yang ditandai dengan terjadinya pemberontakan di berbagai wilayah (Wibawa dalam Dwiyanto,2005;44). Orde Baru yang tampil ke pentas kekuasaan ditahun 1965 masih rapuh dan langsung dihadapkan pada banyak tantangan. Tantangan pertama adalah tuntutan guna menegakan kontrol dan memaksakan otoritas pusat atas seluruh wilayah negara. Kedua, memulihkan stabilitas ekonomi dan meletakan landasan bagi pembangunan ekonomi, dan ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah meletakan legitimasinya sebagai suatu rezim. Ketiga-tiganya merupakan tugas yang sangat berat dan merupakan persoalan pelik bagi Orde Baru selama satu dekade, sebelum akhirnya ia mampu menyongsong dan menyelesaikan (MacAndrews dan Amal,2003;16). Sebagaimana diketahui atau diingat bahwa pada akhir Orde Lama atau awal Orde Baru, kehidupan politik masyarakat dan bangsa begitu tidak stabil (Hasyim,2000;58). Keadaan politik pada saat itu (Orde Lama) sangatlah memperihatinkan, bahkan situasi politik yang tidak stabil, misalnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
114
terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang telah memakan korban sesama saudara dengan jumlah yang tidak sedikit, padahal hanya disebabkan oleh ideologi politik yang berlainan. Usaha pertama yang dilakukan guna mengurangi gejolak rakyat pada lapisan bawah adalah dengan cara membekukan Partai Komunis dan partai yang sealiran dengannya. Kemudian Presiden Soekarno diberhentikan dari masa jabatan Presiden karena pertangungjawabannya ditolak oleh MPRS berkaitan dengan peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI yang merupakan tindak pidana makar (Gunawan,2008;423). Kemudian dalam menjalankan pemerintahan, untuk sementara waktu ditunjuklah Letjen Soeharto sebagai pejabat Presiden sampai adanya pemilihan umum. Dengan kenyataan yang demikian menyiratkan kegagalan Orde Lama dalam melaksanakan tugasnya bahkan menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Masoed dan Andrews (2006;258) menyatakan bahwa dalam bidang politik penguasa Orde Baru menyatakan keinginan untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila secara murni, yaitu sesuai dengan tuntutan dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya ini merupakan koreksi terhadap pemerintahan Soekarno, yang sebelumnya telah banyak melakukan tindakan yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasarnya. Sehingga dapatlah dikatakan kemudian bahwa UUD 1945 merupakan dasar serta arah politik hukum daripada Orde Baru dalam melakukan pembenahan sistem hukum yang sebelumnya tidak jelas ke mana arahnya. Bahkan, menurut Abidin (2005;77) bahwa konfigurasi politik Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno ke konfigurasi politik Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto telah mengubah dengan cepat berbagai politik hukum. Setidaknya terlihat pada awal mula pemerintahan Orde Baru, menunjukan konfigurasi politik hukum yang dapat dipandang cukup responsif, misalnya, dengan melakukan penggantian berbagai produk hukum yang pada dasarnya bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dimulai berjalannya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1965, dalam waktu lebih dari dua warsa terakhir ini telah banyak terjadi perubahan di Indonesia. Perubahan pertama diawali oleh apa yang dikenal sebagai era stabilitas politik dan ekonomi, yang sangat berbeda dengan era instabilitas pada tahun-tahun awal kemerdekaan dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Dengan ini maka terwujudlah integrasi fisik dan nasional, yang juga tidak terlepas dari akibat kemajuan pesat di bidang komunikasi pada semua lapisan masyarakat (MacAndrews dan Amal,2003;1). Bahkan, Zamroni (2007;41) dalam hal ini berpendapat bahwa Orde Baru tampil dalam sejarah politik Indonesia memberikan secercah harapan untuk munculnya kehidupan yang demokratis, dalam sosok demokrasi Pancasila. Pada masa Orde Baru, dengan berpedoman pada pengalaman buruk yang telah terjadi di masa lalu, maka untuk itu segeralah kemudian dikeluarkan sebuah Ketetapan MPRS No.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
115
XXV/MPRS/1966 tentang Larangan penyebaran ajaran komunisme/Leninisme/Marxisme di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, komunisme diyakini ajarannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, bahkan larangan tersebut sampai sekarang pun tetap berlaku. Dengan demikian, tahun 1966 dipandang dari sudut hukum tata negara merupakan era baru dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 (Manan dan Magnar,1997;8). Kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh Orde Baru selanjutnya adalah menghapus campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif dengan dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 1970. Dengan demikian, campur tangan kekuasaan apapun dalam bidang peradilan tidaklah dapat diperkenankan, kecuali masalah tersebut jelas-jelas ditentukan baik dalam undang-undang dasar maupun undang-undang sebagai peraturan pelaksananya. Di samping itu, ditambah dengan dihilangkannya kekuasaan Presiden berupa adanya campur tangannya dalam bidang legislatif terutama terkait dengan tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga ini, apabila tidak tercapainya kata mufakat. Dapatlah dikatakan bahwa pada zaman Orde Baru merupakan upaya koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya pernah dilakukan pada masa Orde Lama, terutama yang tindakan nyata-nyata bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan Orde Baru untuk menegakan UUD 1945, yang mana menurut Kansil dan Christine (2011;70) bahwa pada tahun 1966 dalam SU (Sidang Umum) MPRS menghasilkan antara lain: 1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang mengukuhkan SUPERSEMAR. 2. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang pembaharuan landasan politik luar negeri. 3. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan landasan di bidang ekonomi dan pembangunan. 4. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 mengenai pembubaran PKI dan ormasormasnya. 5. Pada tahun 1967 dalam Sidang Istimewa MPRS dihasilkan antara lain : Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang isinya menarik mandat MPRS dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden
I Gusti Ngurah Santika, SPd
116
(memberhentikan Presiden Soekarno dan mengganti- kannya dengan Pejabat Presiden Soeharto). Selain itu, adanya ketentuan tersebut di atas merupakan upaya koreksi terhadap kesalahan yang pernah dilakukan terhadap Pancasila dan UUD 1945 di masa lalu. Kemudian tindak lanjut lainnya menurut Rindjin (2009;308) yaitu ditambah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.12/1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan Pancasila sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Menurut Mahmud MD (2001;59) penyebab dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, yaitu sebagai berikut. Dalam pada itu sejauh menyangkut materi dekrit ada polemik tentang status Pembukaan UUD 1945 dan Piagam Jakarta. Sebagian orang berpendapat bahwa dengan Dekrit tersebut maka, Piagam Jakarta berlaku kembali; alasannya karena di dalam Konsiderans Dekrit itu disebutkan bahwa Piagam Jakarta merupakan rangkaian dari dan menjiwai UUD 1945. Muatan Konsideran tersebut dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa Piagam Jakartalah yang berlaku karena Konsideranlah yang menyebabkan adanya diktum dari suatu keputusan (seperti Dekrit) itu. Oleh karena itu golongan yang berpendirian seperti itu berpendapat bahwa rumusan Pancasila yang sah berlaku adalah rumusan yang ada di dalam Piagam Jakarta yang sila pertamanya berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya. Tetapi pendapat ini ditolak oleh golongan lain yang lebih berpedoman pada prosedur dan diktum. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968, maka polemik tentang pemberlakuan UUD 1945 kembali melalui Dekrit Presiden tersebut telah berakhir dengan sendirinya. Oleh karena itu, semua penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya dilakukan oleh Soekarno, misalnya saja adanya berbagai peraturan yang pada dasarnya bertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, kemudian semuanya diganti agar tidak lagi bertentangan dengan yang peraturan lebih tinggi, terutama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Rosyadi (2008;125126) berpendapat bahwa dalam konteks ini, Orde Baru ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan. Walaupun pada tahun 1966 UUD 1945 secara resmi telah berlaku selama 11 Tahun, langkah pertama untuk melaksanakannya masih harus dilakukan (Tambunan,1991; 14).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
117
Namun, pernyataan Rosyadi akan berbeda dengan pendapat dari Soemantri (1989;7) yang menyatakan bahwa kalau UUD 1945 itu secara murni dan konsekuen harus dilaksanakan maka kaidah-kaidah yang ada di dalamnya akan menjadi beku. Slogan yang kita sebutkan di atas sebenarnya merupakan reaksi terhadap pengalaman-pengalaman pada masa lalu, di mana UUD 1945 seringkali tidak ditaati atau malahan diselewengkan. Namun janji-janji demokrasi penguasa Orde Baru itu ternyata mendapat dukungan dari berbagai elemen demokrasi, seperti mahasiswa, pers, dan kaum intelektual yang merasa ditindas oleh rezim sebelumnya dengan berbagai produk hukum dan keputusan politik yang membelenggu kebebasan mereka (Abidin,2005;79). Menyambung pernyataan dari Soemantri tersebut di atas, sebenarnya apa yang sebelumnya jadikan jargon oleh Orde Baru tersebut, yang dalam rencananya akan melaksanakan ajaran Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, hanya merupakan sebuah ideologi belaka dari penguasa, yaitu berupa pandangan-pandangan penguasa yang kemudian harus dilaksanakan. Dengan demikian, Orde Baru telah memberi bentuk pandangannya yang bersifat beku tersebut, untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang kelihatan benar, padahal merupakan perbuatan yang bukan saja melanggar konstitusi tetapi juga kemanusiaan. Namun perbuatan tersebut seolah olah legal bahkan konstitusional, karena diberi baju hukum kemudian didukung oleh ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Maka seolah-olah nilai-nilai yang kemudian dianut oleh Orde Baru tersebut, merupakan suatu cerminan yang sepenuhnya benar dan tidak boleh diganggu gugat. Bahkan sebagai pelengkapnya Pancasila dan UUD 1945 selalu dikutip disertai dengan berbagai penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan kehendak penguasa adalah mutlak benar sehingga harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun penafsiran yang diberikan Soeharto berbeda tajam dengan maksud daripada UUD 1945. Namun pada kenyataannya, interpretasi Soeharto atas konstitusilah yang berlaku (Tutik,2008;157). Dengan demikian, ideologi penguasa yang bersifat dominan tersebut, telah menentukan bahkan mereduksi hak rakyat untuk kritis. Dikarenakan oleh penguasa selalu saja memaksa rakyat untuk mengikuti, apa yang kemudian menjadi keinginannya untuk memperoleh kekuasaannya melalui penafsiran-penafsirannya terutama terhadap konstitusi. Kelsen (2010;71) dalam hal ini menyatakan bahwa istilah ideologi yang ambigu tersebut, tentu saja dalam satu kesempatan manandai penegasan cita-cita yang pada dasarnya bertentangan dengan realita, sedangkan dalam kesempatan yang lain menggambarkan sebuah konsep yang menyelubungi realitas dengan merubah bentuk atau menyimpangkannya. Sedangkan pendapat senada dinyatakan oleh Widja (2009;29) bahwa konsep ideologi di sini dimaknai
I Gusti Ngurah Santika, SPd
118
sebagai sistem ide/gagasan untuk mengemas kepentingan kekuasaan tertentu melalui ekspresi budaya. Di sini dimaksud bukan hanya ideologi dalam arti keras dan tertutup, melainkan setiap ajaran dan kepercayaan yang memenuhi definisi di atas (Suseno, 2010;51). Dengan demikian, seharusnya Pancasila didudukan sebagai dasar negara yang pada dasarnya merupakan ideologi negara bahkan bersifat terbuka. Namun, disebabkan oleh adanya prilaku Orde Baru yang dapat dipandang keliru, tetapi selalu saja mengaku bahwa perilakunya tersebut adalah benar, bahkan sudah sesuai dengan jiwa Pancasila. Sehingga pada gilirannya menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap Pancasila, bahkan seolah-olah Pancasila kemudian menjadi ideologi yang bersifat kaku, keras dan tertutup serta jauh dari kehidupan rakyat. Lebih lanjut berkaitan dengan besarnya kekuasaan Soeharto yang sebelumnya diberikan oleh UUD 1945. Maka Marijan (2011;21) kemudian menyatakan dengan tegas bahwa di samping adanya upaya untuk menafsirkan negara Indonesia sebagai berdasarkan paham negara integralistik di dalam pengaturan kekuasaan, munculnya sentralisasi itu juga tidak lepas dari belum begitu jelasnya pemisahan dan pembagian kekuasaan yang ada dalam UUD 1945. Dalam pada itu, dapatlah diketahui dalam UUD 1945 terutama berkaitan dengan pengaturan kekuasaan eksekutif yang pada waktu itu, dipegang oleh Soeharto untuk bertugas menjalankan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Namun, dilain pihak ternyata meliputi juga sebagai pemegang kekuasaan legislatif (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan). Dengan demikian, terlihat seakan-akan adanya dua fungsi yang kemudian dilaksanakan oleh satu lembaga negara dalam UUD 1945. Dapat dipastikan bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang bersifat nyata terhadap sistem pemisahan kekuasaan (separation of power), yang sebenarnya memiliki tujuan utama untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Bahkan dengan terlalu besarnya kekuasaan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945, terutama dalam bidang pembentukan undang-undang menyebabkan seolah-olah lembaga kepresidenan memonopoli tugas lembaga negara lainnya. Dikarenakan jika suatu rancangan undang-undang yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan DPR, ternyata kemudian tidak disahkan oleh Presiden maka rancangan undang-undang tersebut tidak mungkin dapat diundangkan, sehingga otomatis tidaklah bisa berlaku apalagi mau mengikat umum. Dengan besarnya/dominannya kekuasaan Presiden (executive heavy) dalam pemerintahan terutama jika berhadapan dengan kekuasaan DPR, maka ada yang kemudian menyatakan lembaga legislatif hanyalah sebagai lembaga stempel eksekutif. Artinya DPR hanya bertugas untuk mengukuhkan segala tindakan eksekutif dalam bentuk memberikan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
119
persetujuan melulu, tanpa dapat memberikan kritik yang berarti bagi pemerintah sebagai masukan. DPR pada periode ini, benar-benar tidak mampu untuk menjalankan tugas, seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah lembaga perwakilan, yang memang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Biasanya sebagai sebuah lembaga perwakilan dalam negara demokrasi, DPR setidaknya harus berusaha untuk memperjuangkan kehendak rakyat. Bahkan, DPR haruslah berusaha untuk menjadikan kepentingan rakyat sebagai sebuah kebijakan baik dalam pengawasan maupun dengan bentuk undang-undang. Namun, dalam kenyataannya pembentukan undang-undang pada waktu itu benar-benar di dominasi oleh Presiden, bahkan dapatlah dikatakan bahwa tidak ada satupun undang-undang yang lahir dari inisiatif murni DPR selama Orde Baru berkuasa. Kesimpulan yang mungkin dapat diperoleh dari paparan tersebut di atas, dapat dipetikan kemudian dari kalimat Asshiddiqie dan Manan (2006;7) yang menyatakan bahwa struktur UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasan eksekutif. Karena itu, sering muncul anggapan bahwa UUD 1945 sangat executive heavy. Presiden tidak hanya sebagai pemegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan (chief executive), tetapi juga menjalankan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Faktor lainnya yang ikut menentukan serta menjadi penyebab utama tidak mampunya DPR dalam mengimbangi kekuasaan Presiden. Ternyata disebabkan oleh adanya rekruitmen anggota DPR yang tidak dapat dibenarkan, jika kemudian diukur dari sudut demokrasi, yang pada dasarnya menjungjung tinggi cara-cara demokratis. Dengan demikian, Orde Baru telah merekayasa dalam pembentukan lembaga DPR, yang sebenarnya lembaga ini merupakan representasi dari rakyat berdaulat. Bahkan, tidak demokratisnya tindakan Presiden tersebut, terlihat sangat jelas terutama dengan adanya pengangkatan sebagian besar terhadap keanggotaan DPR, telah menyebabkan tidak kritisnya DPR terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya menyimpang dari pemerintah. Padahal telah diketahui oleh umum bahwa banyak tindakan dari pemerintah kemudian yang dilakukan sesuai dengan undang-undang, namun undang-undang tersebut justru jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasarnya. Dengan demikian, pada awal mula pemerintahannya, Soeharto telah berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, namun ternyata tidak sesuai dengan slogan yang sebelumnya selalu saja didengung-dengungkan dalam setiap pidatonya. Tidak hanya penyimpangan seperti tersebut di atas, yang sebelumnya dilakukan oleh Orde Baru, hal itu dapat terjadi tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang sebenarnya melekat pada UUD 1945. Namun, Orde Baru kemudian mencoba untuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
120
memberikan tafsir-tafsir tunggal yang pada dasarnya adalah tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945. Penafsiran tunggal terhadap Pancasila dan UUD 1945 secara sepihak, memang merupakan pernyataan yang dapat dipandang tepat sekali untuk kemudian menggambarkan keadaan pada waktu pemerintahan Orde Baru. Karena setelah berhasil mengkonsolidasikan dan mampu mengukuhkan kekuasaan yang baru saja diperolehnya, Orde Baru ternyata mulai menunjukan sifat negatif dari yang namanya sebuah kekuasaan. Pada dasarnya berbagai bentuk penyimpangan sebelumnya dilakukan oleh Orde Baru terhadap UUD 1945, tetapi dengan mengatas namakan UUD 1945, seolah-olah UUD 1945 didudukan sebagai dasar hukumnya bagi tindakannya yang salah tersebut. Meskipun tentang persepsi kebenarannya yang perolehnya dari UUD 1945, hanya dengan penafsiran yang bersifat sepihak, kemudian disertai pula dengan ancaman, bahkan dalam bentuk ekstrimnya berupa kekerasan bagi pihak-pihak yang kemudian menentang penafsirannya tersebut. Permasalahan dalam hal ini, menurut pendapat Naim dan Sauqi (2010;133) ialah mengenai persoalan perbedaan tafsirmenjadi problem pelik tatkala ada pihak yang menganggap bahwa otoritasnya saja yang paling berhak untuk menginterpretasikan teks suci dan hanya tafsirnya yang paling valid dan benar, sedangkan tafsir orang lain dianggap salah. Dapatlah kemudian diberikan contoh, terkait dengan penafsiran Orde Baru terhadap ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam mana ketentuan tersebut sebelumnya tidak secara tegas membatasi masa jabatan Presiden dalam periode tertentu. Dengan adanya ketidak pastian hukum tersebut, Soeharto kemudian menafsirkannya dengan menyatakan bahwa seorang Presiden menurut ketentuan tersebut, dapat saja memegang kekuasaan selama dia dipilih kembali oleh MPR. Dengan demikin, batasan yang secara implisit dinyatakan dari ketentuan UUD 1945 dan juga dari pernyataan Soeharto, bahwa batasan terhadap masa jabatan presiden adalah sangat tergantung daripada kehendak MPR. Padahal banyak yang kemudian menyatakan bahwa Presiden seharusnya hanya boleh menjabat sebanyak dua periode, yang selanjutnya tidak dimungkinkan kembali untuk dapat dipilih oleh MPR. Tafsiran dari Orde Baru inilah yang kemudian menyebabkan periode kekuasaan yang sebelumnya telah dipegang oleh Soeharto cukup lama, yaitu dalam waktu 32 tahun. Bahkan, dengan tidak pernah berpindahnya kekuasaannya, yang kemudian dapat dikatakan hanya berputar-putar di sekitarnya. Pada akhirnya telah menimbulkan pula kekuasaan yang bersifat sangat mutlak, tanpa ada yang kemudian mampu mengawasi dan mengimbanginya, apalagi selanjutnya hendak berniat untuk membatasinya. Namun, sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa terkait dengan masalah penafsiran, maka hanya penafsiran dari penguasalah yang kemudian dapat menjadi pedoman. Karenakan hanya penguasa yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
121
mempunyai kemampuan untuk membuat menurutnya benar.
dan menegakan sejarah yang memang
Berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pada waktu Orde Baru menjadi penguasa, adalah besarnya peranan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945 dalam sistem pemerintahan presidensial membuat Soeharto menjadi tokoh yang dapat dikatakan paling dominan. Terlihat pula dari berbagai keputusan yang penting kemudian diambil oleh Presiden Soeharto, terutama yang menyangkut dalam bidang ketatanegaraan adalah secara mutlak benar dan tidak dapat diganggu gugat, walaupun pada kenyataannya keputusan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, sebagai dasar dari keputusannya yang sebelumnya diambil. Kemudian Mufid (2007;113-114) berpendapat bahwa era Orde Baru ditandai dengan begitu kuatnya sistem presidensialisme, bahkan melebihi apa yang pernah dilakukan Soekarno dulu. Kekuasaan sedemikian terpusat pada Presiden, yang sekaligus merangkap ketua dewan pembina partai mayoritas. Tentunya tindakan yang sebelumnya dilakukan oleh Soeharto berbeda dengan Soekarno, dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Dimana sebenarnya Soeharto dengan kejeliannya berusaha untuk memanfaatkan berbagai kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 disatu pihak, sehingga akhirnya mampu menumpuk seluruh kekuasaan untuk kemudian berada di tangannya. Meskipun ketika itu ada lembaga MPR sebagai lembaga negara yang kedudukannya tertinggi, sehingga berada di atas Presiden, yang kemudian bahkan dapat meminta pertanggungjawaban Presiden, namun dalam kenyataannya tidaklah dapat membendung kekuasaan besar yang dimiliki oleh Presiden. Hal ini terjadi tidak lain dikarenakan adanya sistem pengangkatan terhadap anggota perwakilan baik untuk di DPR maupun MPR. Dimana seharusnya badan ini merupakan pengawas utama terhadap kekuasaaan Presiden agar tidak cenderung menjadi menyimpang terhadap UUD 1945. Namun dalam kenyataannya, DPR dan MPR tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan fungsinya, seperti apa yang diharapkan oleh UUD 1945. Pengangkatan terhadap keanggotaan DPR dan MPR yang dilakukan selama ini oleh Soeharto, merupakan suatu bentuk penyimpangan konstitusional terhadap sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Bahkan merupakan bentuk penyalagunaan kekuasaan (abuse of power) dalam praktek ketatanegaraan, yang biasanya hanya dianut oleh negara-negara dengan bentuk pemerintahan diktaktor/otoriter. Bahkan, Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang telah meletakan sendi-sendi kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, mestinya suara rakyat tersebut mendapatkan tempat yang semestinya. Bahkan, tentunya rakyat lewat suaranya adalah berdaulat untuk kemudian memilih wakil-wakilnya, yang selanjutnya akan mewakili
I Gusti Ngurah Santika, SPd
122
mereka untuk duduk di DPR dan MPR dalam memperjuangkan semua aspirasinya. Dengan demikian, rakyatlah yang seharusnya secara langsung menentukan siapa saja yang kemudian berhak untuk mewakili mereka dalam memperjuangkan aspirasinya, serta mengawasi berbagai tindakan pemerintah yang dapat saja merugikan hak-hak rakyat, padahal terlihat dengan jelas bahwa hak rakyat tersebut telah dijamin oleh UUD 1945. Ketidak konsekuenan Presiden Soeharto di dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan UUD 1945, dapatlah kemudian dilihat dalam bentuk pengangkatan DPR dan MPR yang ketika itu sebagian besar anggotanya ditunjuk oleh Presiden, yang tentu nantinya akan menjalankan kehendak-kehendak Presiden dalam berhadapan dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya berdaulat. Berbagai tindakan Soeharto tersebut pada dasarnya adalah bertentangan sekali dengan semangat serta jiwa demokrasi. Bahkan, dalam berbagai bentuk dan usaha yang kemudian dilakukan untuk mencari dukungan berupa pembenaran-pembenaran semu, dengan mengajak kaum intelektual dalam mendukung penafsiran sepihak terhadap UUD 1945, yang sebelumnya diberikan oleh Presiden sebagai sesuatu yang mutlak kebenarannya. Seperti dapatlah dicontohkan, berkenaan dengan pemberian kursi oleh Presiden kepada ABRI di DPR dan MPR, yang mana dulunya adalah sesuai dengan doktrin Dwi Fungsi ABRI yang berlaku ketika itu. Di mana ABRI selain memiliki tugas dan fungsi pertahanan dan keamanan, ternyata juga mempunyai fungsi sosial dan politik. Bahkan ABRI yang ada di DPR dan MPR dapat juga membentuk sebuah fraksi, seperti partai politik yang lainnya. Tetapi jika dicermati dengan saksama berkaitan antara jumlah anggota ABRI yang diangkat untuk duduk di DPR dan MPR pada waktu itu adalah tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan anggota ABRI di tanah air. Tentu tidak sesuainya di sini dapat diperoleh dengan membandingkannya sistem pemilihan umum yang digunakan pada waktu itu, yaitu sistem proporsional. Alasan kenapa kemudian ABRI mendapatkan jatah kursi di badan perwakilan adalah untuk tetap menjaga netralitas ABRI dengan menghilangkan haknya berpolitik, yaitu untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Namun, selain itu alasan ABRI ikut diangkat oleh Presiden dalam lembaga MPR dan DPR adalah ditafsirkan dari isi Penjelasan UUD 1945, terutama dengan adanya kata utusan golongan. Dengan memasukan ABRI sebagai salah satu daripada utusan golongan sebagaimana dimaksudkan di atas, adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kemauan sebenarnya dari Penjelasan UUD 1945. Karena yang dimaksudkan dalam Penjelasan UUD 1945, terkait dengan utusan golongan adalah hanya termasuk golongan koperasi, serikat pekerja. Dengan demikian, Orde Baru telah memperluas tafsir dari Penjelasan UUD 1945 tersebut, dengan memasukan ABRI sebagai salah satu unsur keanggotaannya di MPR. Namun, tentunya, jika berkaitan dengan masuknya ABRI dalam MPR yang di dapat hanya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
123
berdasarkan penafsiran daripada Penjelasan UUD 1945. Sedangkan bagaimana dengan keanggotaannya di DPR, yang ternyata juga memberikan kursi kepada ABRI bahkan dengan membentuk sebuah fraksi? Tentunya kita akan bertanya kembali darimanakah legalitas ABRI untuk kemudian mendapatkan kursi di DPR padahal ABRI merupakan wakil dari golongan, sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan UUD 1945, tentang keanggotaan MPR, bukan dalam hal keanggotaan DPR. Dilain pihak ternyata lembaga-lembaga negara lainnya yang secara yuridis konstitusional seharusnya memiliki kedudukan sejajar dengan Presiden, seperti DPA, MA, BPK, ternyata tidaklah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dikarenakan dalam kenyataannya fungsi lembaga negara tersebut, telah terkooptasi oleh kekuasaan presiden yang ketika itu cenderung mengarah menjadi sewenang-wenang, cara yang dilakukannya adalah dengan menempatkan kaki tangannya (orang yang dekat dengan Orde Baru) di lembaga-lembaga negara tersebut. Tidak berdayanya lembaga-lembaga negara dalam melakukan fungsi dan tugas agar sesuai dengan amanat UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya, dikarenakan adanya tindakan opresif yang sebelumnya dilakukan oleh Soeharto terutama terhadap orang yang nyata-nyata berani menentangnya. Taktik yang ketika itu digunakan oleh Orde Baru agar supaya penyimpangannya secara yuridis konstitusional, tidak terlihat secara gambling, adalah dengan merekayasa pembentukan undang-undang, sehingga seolah-seolah tidaklah kemudian melanggar undang-undang. Dengan demikian, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya oleh Soeharto untuk kemudian mengatur kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara tersebut, telah menjadi pembenar bagi Presiden dengan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk selanjutnya mereduksi fungsi dan tugas kelembagaan negara sebagaimana dimaksudkan UUD 1945, sehingga tidak mampu untuk berbuat banyak terutama dalam berhadapan langsung dengan pihak eksekutif. Semua itu dapat terjadi, tidak lain disebabkan kelemahan yang pada dasarnya memang melekat pada UUD 1945. Karena UUD 1945 sesungguhnya terlalu banyak mengatribusikan kekuasaannya kembali kepada undang-undang untuk kemudian mengatur lebih lanjut ketentuan dari UUD 1945, termasuk juga berkenaan dengan kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga negara lainnya. Kesempatan itulah yang kemudian tidaklah disia-siakan oleh Orde Baru, dimana pada waktu itu Presiden selain berfungsi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), ternyata juga secara tidak langsung ditentukan merupakan kepala daripada lembaga legislatif, dikarenakan dalam kenyataannya ditentukan memegang kekuasaan membentuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
124
undang-undang (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Baru adalah bersifat mutlak. Karena tidak ada yang kemudian dapat banyak dilakukan oleh lembaga negara lainnya, termasuk rakyat sendiri sebagai pemegang kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya, untuk kemudian menghentikan semua tindakan Orde Baru, yang pada dasarnya sangatlah menyimpang terhadap UUD 1945. Bahkan, yang kemudian sangat disayangkan kembali adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan berupa penyimpangan yang terjadi berlebih-lebihan, sehingga kemudian mengakibatkan hak-hak politik rakyat menjadi terdesak dan terpinggirkan. Kekuasaan pemerintah Orde Baru selama lebih dari dua puluh lima tahun telah secara amat ketat mengontrol hak-hak politik rakyat yang meliputi, antara lain hak kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan hak atas imformasi. Sebagai akibat dari kontrol politik pemerintah, rakyat menjadi tidak berdaya untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sebagai akibatnya perilaku kekuasaan berjalan di luar kontrol rakyat. Dan ini membawa akibat terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (Nusantara,2005;xvii). Tidaklah heran kemudian jika ternyata hal tersebut terjadi, dikarenakan oleh besarnya tumpuan kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh Orde Baru, sehingga mampu menopangnya untuk selanjutnya bertentengger di atas kursi kepresidenan, dalam periode yang cukup lama, seperti adanya dukungan dari Golkar, ABRI, dan Birokrasi (ABG) yang kemudian menyebabkan kekuasaannya menjadi semakin dominan. Dengan ketiga mesin politik di atas, membuat Orde Baru seakan-akan memiliki kekuasaan super power, yang tentunya tidak akan dimiliki lembaga negara lainnya. Kehidupan demokrasi ketika itu tidaklah dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena hasil rekayasa dari ketiga mesin Orde Baru yang sebenarnya telah merancang sedemikian rapinya, sehingga nyaris tidaklah terlihat. Tujuannya tentu tidak lain agar Orde Baru tetap berkuasa, terutama untuk dapat duduk secara terus menerus dalam kursi kepresidenan. Bahkan, kekerasan politik merupakan sesuatu yang dipandang sudah biasa, sehingga dapat diketahui bahkan disaksikan secara nyata dan merupakan pemandangan yang sudah lumrah di negeri ini pada periode tersebut. Hal tersebut dilakukannya sebagai upaya untuk menutupi kedok palsunya, alasan yang utama menurutnya agar stabilitas politik tetap terjaga. Padahal semua hal tersebut dilakukan penguasa dengan tujuan agar tetap mampu untuk mempertahankan kekuasaan bahkan tidak segan-segan dengan membungkam semua lawan politiknya agar tidak ada yang dapat menghalanginya dikemudian hari. Dengan demikian, terkait situasi dan kondisi politik ketika itu, menurut MacAndrews dan Amal (2003;17) bahwa stabilitas politik dalam tahun-tahun awal Orde
I Gusti Ngurah Santika, SPd
125
Baru dicapai melalui proses depolitisasi yang ditandai oleh sejumlah pambatasan atas aktivitas-aktivitas politik yang pada gilirannya, mengakibatkan surutnya peranan partaipartai politik. Bahkan, pada awal-awal dimasa kepemimpinan Orde Baru memang kekuatan-kekuatan politik masih dapat bernafas dengan lega terutama kebebasan mendirikan partai politik. Namun, tentunya pemerintah sebelumnya sudah memiliki bekal berupa persepsi terhadap partai politik, yang pada waktu itu menurut pemerintahn, merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab dari instabilitas jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, pada tahun 1971 pemerintah kemudian menganjurkan agar partai-partai politik segera melakukan fusi (penggabungan), sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam melaksanakan programnya atau dibubarkan saja. Akhirnya, pada tahun 1973 barulah kemudian partai-partai politik dapat melakukan fusi, sesuai dengan apa yang sebelumnya menjadi anjuran daripada Soeharto. Dimana partai-partai politik tersebut kemudian berfusi menjadi tiga partai politik, yang mana sebelum bergabung/fusi partai politik pada waktu itu berjumlah sepuluh partai politik. Setelah diadakannya fusi, maka dapatlah kemudian dikatakan bahwa pada periode pemerintahan Orde Baru, sistem kepartaian yang memang digunakan pada waktu itu adalah sistem kepartaian dengan multipartai terbatas. Tidak lain, dikarenakan jumlah partai politik yang ikut terlibat dalam kegiatan politik adalah lebih dari dua partai politik, namun dalam kenyataannya telah ditentukan pula, hanya tiga organisasi politiklah yang kemudian diperkenankan ikut terlibat untuk selanjutnya berpartisipasi dalam mengikuti pemilu. Dan dapatlah dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan oleh Orde Baru merupakan suatu sistem pemerintahan negara yang pada prinsipnya mengandung ciri otoriter. Dikarenakan adanya pembatasan oleh penguasa terhadap kebebasan rakyat untuk kemudian mendirikan organisasi politik, terutama partai politik. Bahkan di samping itu, tindakan tersebut juga tentunya telah mengekang kebebasan rakyat dalam menentukan pilihannya, terutama terhadap partai politik yang dikehendaki untuk kemudian dijatuhkan sebuah pilihan, yang tentunya sesuai dengan keinginan para pemilih. Meskipun, dalam kenyataannya adanya tiga organisasi politik waktu itu yang diwakili oleh PPP, PDI, Golkar, yang kemudian menurut Ahmadi dan Uhbiyati (2003;186) bahwa organisasi politik seperti PPP, PDI dan juga Golkar pada masa-masa tertentu melakukan aktivitas untuk mempengaruhi massa. Namun, dalam kenyataannya di lapangan hanya Golkarlah yang kemudian benar-benar mampu dan efektif untuk mempengaruhi masa yang berada pada tingkat bawah. Yang selanjutnya dibuktikan dengan kemenangan-kemenangan yang diperolehnya, pada saat pemilihan umum dari beberapa sejarah perjalanan pada periode selama ini. Hal tersebut dapat terjadi, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang sebenarnya bersifat memihak kepada salah satu
I Gusti Ngurah Santika, SPd
126
kontestan. Dengan adanya dukungan pemerintah terhadap Golkar, tentunya telah menyebabkan kontestan yang lainnya, tidak mampu untuk berbuat banyak terutama dalam keterlibatannya untuk menghadapi kompetisi secara sehat. Dengan demikian, adanya pemilihan umum hanyalah sekedar prosedur formal semata, dikarenakan sudah dapat dipastikan kemudian, siapakah yang nantinya akan menjadi pemenang pemilu. Dengan berbagai pembatasan yang ditujukan terhadap ruang gerak PDI dan PPP, telah menyebabkan kedua partai politik tersebut, tidak berdaya dalam usahanya untuk meraih suara pemilih dipesta demokrasi yang diselenggarakan tersebut. Padahal pemilu legislatif yang sebelumnya diikuti oleh dua partai politik tersebut, adalah dengan tujuan untuk mendapatkan kursi di DPR, guna selanjutnya berhadapan secara langsung dengan pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Berbagai bentuk pembatasan yang ditujukan hanya pada dua partai politik tersebut, sedangkan Golkar dilain pihak dapat saja melakukan kegiatan politik secara bebas untuk kemudian mempengaruhi suara pemilih sampai ke pelosok desa. Bahkan cara-cara yang digunakan oleh Golkar, baik melalui cara yang bersifat demokratis sampai kemudian pada tekanan-tekanan yang dapat dikatakan bersifat terbuka, tentunya semua itu dilakukannya dengan adanya bantuan dari aparat pemerintahan terbawah. Memang pada waktu itu, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang ditopang oleh kekuatan dari Partai Golkar setidaknya telah berhasil membangun perekonomian negara, juga ditambah adanya lembaga-lembaga politik yang makin mantap, bahkan bersifat sangat professional dalam menjalankan kegiatan politiknya. Sudah jelas bahwa profesionalisasi, pembangunan ekonomi dan makin kuatnya lembaga politik seperti Golkar, mengharuskan adanya pemikiran baru tentang bentuk co-ruler yang diinginkan (Magenda,2000;XXXIX). Bahkan, pada zaman pemerintahan Orde Baru telah timbul pula, pemikiran-pemikiran bahkan tindakan yang kemudian pada dasarnya tidaklah dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat demokratis. Dimana pada ada waktu itu Orde Baru melakukan tindakan-tindakan yang semangatnya sangatlah bertentangan dengan jiwa demokrasi. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan golkar dalam pemilu seperti adanya prinsip monoloyalitas terhadap pegawai negeri, yang bertujuan untuk mendukung Orde Baru, maka semua pegawai negeri dilarang untuk masuk menjadi partai politik, karena diharuskan untuk ikut bergabung dan memilih golkar dalam setiap pemilu. Dengan demikian, kedudukan pegawai negeri yang memang seharusnya netral terhadap kegiatan politik aktif, kemudian berubah menjadi tidak netral, karena ditentukan untuk memihak kepada salah satu kontestan pemilu, yang bahkan diwajibkan untuk ikut terlibat dengan bergabung dalam tubuh Golkar. Padahal tujuan awal mula dari prinsip monoloyalitas hanyalah merupakan kebijakan dalam rangka melindungi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
127
Orde Baru dari musuh-musuhnya, namun ternyata kebijakan ini teruslah disalah gunakan dengan diterapkannya dalam setiap pemilihan umum. Bukti tersebut dapatlah kemudian menjelaskan bahwa partai politik sebagai salah satu infrastruktur dalam negara demokrasi, bahkan sebenarnya merupakan pilarnya utama demokrasi, ternyata tidak berdaya dalam melakukan checks and balances terhadap suprastruktur. Akibatnya, infrastruktur yang seharusnya memiliki peran tidak kecil yang mana sebelumnya terlibat aktif dalam membentuk suprastruktur, selanjutnya mengadakan pengawasan, agar kemudian tidak menyimpang dari tujuan semula dibentuknya suprastruktur tersebut, sehingga nantinya dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, dengan berbagai tindakan tidak adil yang kemudian dilakukan dalam proses demokrasi ternyata berimbas pula, terhadap lembaga-lembaga demokrasi lainnya yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Bahkan akibatnya adalah konfigurasi yang kemudian dihasilkan berupa sistem pemerintahan yang berwatak otoriter, konservatif serta elitis. Hal mana dapat diketahui kemudian dari undang-undang yang selanjutnya merupakan hasil dari lembaga legislatif pada zaman Orde Baru yang pada hakekatnya hanyalah melayani kepentingan daripada penguasa. Hukum dimanipulasi menjadi hamba sahaya segelintir penguasa,pemanipulasian ini terjadi karena Presiden Soeharto menguasai nyaris semua kekuasaan negara (Tutik,2008;156). Pada dasarnya, dengan keluarnya berbagai peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sebenarnya hanya bertujuan, yaitu untuk dapat mempertahankan serta kembali mengukuhkan kekuasaan yang memang telah lama berada di dalam genggamannya. Inilah merupakan salah satu strategi jitu daripada Orde Baru dalam mempertahankan kekuasaan, yaitu dengan cara mengganti semua produk peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung kedudukan penguasa, kemudian berusaha untuk mengukuhkan peraturan lama yang tentunya dapat menunjang serta menopang kekuasaannya. Dapatlah diberikan suatu contoh, dengan adanya Ketetapan MPR yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan jiwa UUD 1945, kongkretnya dengan ketentuan Pasal 37 tentang peraturan yang secara garis besarnya mengatur tata cara perubahan terhadap UUD 1945, oleh MPR. Bahkan, dalam kenyataannya terdapat dua Ketetapan MPR yang bertujuan menghalangi terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, yaitu pertama adanya Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum, kemudian disusul dengan adanya Tap MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Keluarnya ketetapan ini tidak lain dilatar belakangi dengan begitu banyaknya protes tentang besarnya pengangkatan terhadap keanggotaan DPR dan MPR oleh Presiden Soeharto. Dilain pihak, pengangkatan tersebut telah menjadi penyebab tidak
I Gusti Ngurah Santika, SPd
128
mampunya kedua lembaga negara tersebut untuk kemudian melaksanakan fungsinya sebagaimana biasanya yang sering dilakukan sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat. Namun, pemerintah berdalih tentang adanya pengangkatan tersebut, dengan menurutnya merupakan alasan yang sangat prinsipil, yaitu dengan tujuan untuk mempertahankan dan mengukuhkan kedudukan Pancasila dan UUD 1945, yang berarti komitmen pemerintah agar Pancasila tidak akan menggantinya dengan ideologi apapun lainnya. Dikeluarkanlah kedua Tap MPR tersebut, dengan dalih utamanya adalah untuk tetap mempertahankan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yang merupakan norma fundamental negara (staatfundamentalnorm), dengan akibat jika dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 terutama terhadap Pancasila, kemudian akan menjadi penyebab bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sebagai dispensasi dari dikeluarkannya kedua ketetapan MPR tersebut di atas, yang sebenarnya menghalangi perubahan terhadap UUD 1945, maka untuk ke depannya Soeharto akan melakukan peninjauan kembali terkait tentang besarnya pengangkatan anggota DPR dan MPR. Karena pada awalnya memang pengangkatan anggota DPR dan MPR adalah untuk mengawal UUD 1945, yang kemudian di dalam alenia ke empat terdapat Pancasila sebagai ideologi negara yang perlu untuk kemudian dipertahankan dan dilestarikan. Kata peninjauan tersebut di atas, belum berarti benar-benar akan mengurangi jumlah anggota DPR dan MPR yang nantinya akan diangkat oleh Presiden Soeharto. Namun, tampaknya ucapan-ucapan Presiden Soeharto tersebut, hanyalah merupakan suatu pernyataan dibibir saja, yang pada dasarnya bertujuan sebagai pengembira. Padahal yang kemudian menjadi tujuan sebenarnya adalah untuk menenangkan sementara waktu hati rakyat yang merasa gelisah, bahkan tidak puas dengan sistem pengangkatan wakil-wakil mereka seperti di atas. Sedangkan, dalam kenyataannya masih saja berlangsungnya pengangkatan terhadap pengisian keanggotaan di DPR dan MPR yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden. Perlu diketahui, sepanjang perjalanan periode ini terlihat banyak peraturan yang posisinya berada di bawah UUD 1945 yang kemudian pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Kemudian peristiwa inilah selanjutnya menimbulkan berbagai bentuk protes terutama dari kalangan ahli hukum, maka lahirlah gagasan-gagasan serta berkembang luas dimasyarakat untuk masalah itu. Salah satunya gagasan tersebut, yang dapat dikatakan cukup penting untuk kemudian dikemukakan di sini, adalah adanya usul untuk memberikan hak uji materiil peraturan perundang-undangan (toetsingrecht) kepada MA. Bahkan, sebenarnya pemikiran hak uji materiil telah timbul jauh hari sebelum
I Gusti Ngurah Santika, SPd
129
Indonesia merdeka, kemudian permikiran ini timbul kembali setelah jatuh Orde Lama dari kekuasaannya. Ketika itu, pengkajian yang berhasil dilakukan oleh MPR terhadap UUD 1945 setelah jatuhnya Soekarno. Namun, patut disayangkan bahwa hasil dari kajian MPR tersebut akhirnya ditolak mentah-mentah oleh pemerintah. Berkaitan dengan penolakan pemerintah terhadap usul yudicial review yang kemudian didasarkan pada alasan bahwa UUD 1945 tidaklah menganut sistem ketatanegaraan, yang mengadakan pemisahan kekuasaan, seperti apa yang berlaku di Amerika Serikat. Di mana dalam negara Amerika Serikat adanya pemberian kewenangan kepada lembaga negara yang bernama Supreme Court untuk kemudian menguji undang-undang, baik yang telah dibuat oleh Kongres maupun undang-undang dibentuk oleh negara bagian terhadap konstitusi federal (constitutional review). Akhirnya, terkait berbagai pendapat yang bersifat pro dan kontra tentang adanya usul yudicial review, kemudian mendapatkan jawaban tegas dari pemerintah, yaitu dengan keluarnya UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan keluarnya UU No. 14 Tahun 1970, telah menegaskan sikap pemerintah berkaitan dengan hak menguji undang-undang terhadap UUD 1945, oleh Mahkamah Agung. Pada dasarnya ketentuan dalam UU tersebut intinya menyatakan bahwa MA tidaklah memiliki wewenang untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Dikarenakan jika ingin meletakan kewenangan pengujian undang-undang seharusnya tercantum secara jelas dalam UUD 1945, lagipula menurut UU, MPR pada waktu itu belumlah memberikan hak uji kepada MA. Bahkan dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa dengan tidak adanya ketentuan peraturan yang mengatur mengenai hak uji undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut, maka tidaklah dengan sendirinya MA dapat melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Pengujian yang diakui oleh UU 14 Tahun 1970, yaitu hanya pada tingkat di bawah undang-undang terhadap UU, bahkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tersebut, hanya dapat dilakukan kemudian pada tingkat kasasi. Sedangkan untuk pencabutan keberlakuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang telah diuji oleh MA, dilakukan oleh instansi yang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kenyataannya, sejak adanya kewenangan yang melekat pada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sampai dengan jatuhnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya, memang belumlah pernah ada satu produk hukum pun berupa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung. Tidak lain, dikarenakan adanya kekacauan teoritis yang memang disengaja oleh pembuat undang-undang sendiri, agar apa yang kemudian
I Gusti Ngurah Santika, SPd
130
tercantum dalam ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, tidak mungkin dapat untuk dioperasionalkan sebagaimana mestinya. Bahkan, lebih aneh lagi bahwa undang-undang tersebut, telah menentukan dengan tegas bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sebelumnya diujikan di Mahkamah Agung, yang kemudian oleh Mahkamah Agung dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, maka bukanlah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan secara langsung untuk mencabutnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut, melainkan merupakan kewenangan dari instansi yang membuatnya lah yang ditentukan memiliki kewenangan untuk selanjutnya mencabut peraturan yang telah diuji tersebut. Ini berarti bisa saja instansi yang sebelumnya membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut, tidak mau mematuhi putusan dari Mahkamah Agung untuk kemudian mencabut peraturan yang sebelumnya telah dinyatakan batal tersebut. Terus siapakah yang kemudian dapat memaksakan kepada instansi yang membentuk peraturan tersebut agar mau mencabutnya? Makna tidak tidak lain: kekuasaan tertinggi atas hukum tidak dipengadilan, tetapi di tangan birokrasi (Lev,2013;382). Kemudian kita kembali pada pembahasan tentang prosedur perubahan terhadap UUD 1945, yang pada dasarnya telah ditentukan dengan tegas dalam ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Ternyata kemudian akan terlihat berbeda pula, dengan ketentuan di bawahnya yang dalam kenyataannya juga mengatur tata cara perubahan terhadap UUD 1945, seperti yang terlihat kemudian dalam Tap MPR No. IV/MPR/1983. Berkaitan dengan adanya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983, kemudian dalam ketentuan Pasal 2 ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 itu menentukan, apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum ketentuan Pasal 3 menentukan, refrendum dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR yang diatur dengan undang-undang sedangkan dalam Pasal 4 Ketetapan ini dinyatakan, dengan ditetapkannya Ketetapan tentang Refrendum ini, maka ketentuan Undang-Undang mengenai pengangkatan 1/3 anggota Majelis ditinjau kembali menurut Jimly Asshiddiqie (2006;174) bahwa dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan operasional mengenai penyelenggaraan refrendum itu masih harus dielaborasi dalam undang-undang. Akan tetapi secara umum dapat diketahui bahwa tujuan refrendum itu adalah untuk meminta pendapat rakyat apakah rakyat menyetujui atau tidak menyetujui kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945. Bahkan prosedur Perubahan UUD 1945, yang berkaitan persyaratan suara sebelumnya yang terlebih dahulu harus dicapai dalam melakukan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
131
referendum tersebut, adalah menyebabkan sangat kecil kemungkinan untuk MPR dalam menjalankan kewenangannya, agar kemudian mampu mengubah UUD 1945. Bahkan, dalam ketetapan MPR tersebut ternyata semakin mempersulit prosedur perubahan terhadap UUD 1945, bila kita dibandingkan kemudian dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Karena, jika seandainya suara rakyat dalam referendum tersebut ternyata telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan, maka tidaklah secara otomatis akan dapat melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Dikarenakan tentunya MPR masih akan bersidang kemudian, untuk selanjutnya memutuskan kembali, apakah MPR berkehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau tidak. Jadi, pada akhirnya suara yang sebelumnya diberikan rakyat dalam referendum, dalam kenyataannya tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, melainkan MPR lah yang memang masih tetap memiliki kewenangan tersebut. Hanya saja, rakyat berkaitan dengan hal ini memiliki hak untuk terlibat secara langsung berupa pemberian suara guna menolak perubahan terhadap UUD 1945, yang mungkin akan dilakukan oleh MPR. Cara rakyat menolak perubahan terhadap UUD 1945, adalah dengan persyaratan suara kurang yang dicapai sebelumnya daripada ketentuan dalam ketetapan MPR tersebut. Maka selanjutnya MPR tidaklah berwenang untuk kemudian melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, suara rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam ketetapan MPR tersebut, adalah merupakan suatu persetujuan untuk kemudian memberikan jalan dalam melakukan perubahan UUD 1945, yang nantinya ingin dilakukan oleh MPR, yang sebenarnya memang memiliki kewenangan, seperti apa yang dimaksudkan kemudian dalam ketentuan Pasal 3 jo 37 UUD 1945. Tetapi ketentuan Tap MPR tersebut, sangat bertentangan dengan jiwa daripada UUD 1945, khususnya yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur terkait dengan prosedur MPR, dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa inti daripada adanya ketentuan pengaturan tentang Perubahan UUD 1945, berupa keluarnya kedua ketetapan MPR tersebut, adalah bertujuan untuk semakin mempersulit prosedur perubahan terhadap UUD 1945. Selain keluarnya dua ketetapan MPR tersebut di atas, untuk lebih lanjutnya juga dikeluarkan kembali peraturan yang kedudukannya lebih operasional daripada ketetapan MPR tersebut, terkait dengan prosedur perubahan terhadap UUD 1945 melalui referendum. Dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 1985, yang merupakan suatu ketentuan di mana isinya lebih teknis dalam pelaksanaan referendum dikemudian hari, jika memang hendak dilaksanakannya perubahan terhadap UUD 1945. Dengan lahirnya berbagai peraturan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
132
perundang-undangan, yang pada dasarnya menghalangi terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, secara tidak langsung telah menyebabkan pula, UUD 1945 mengalami sakralisasi yang luar biasa. Dalam kenyataannya tidaklah ada yang kemudian berani untuk menyinggung, terutama mempermasalahkan tentang pengaturan perubahan terhadap UUD 1945 tersebut. Karena hal itu berarti sama saja dengan menentang pemerintah, yang berarti juga bisa dikatakan telah melakukan tindakan subversi (makar) terhadap pemerintahan yang sah. Dengan demikian, sakralisasi terhadap UUD 1945, telah menyebabkan undang-undang dasar tidaklah dapat disentuh oleh perubahan, walaupun hanya sekedar sebuah ide, apalagi kalau ide tersebut kemudian dilontarkan, yang kemungkinan dikemudian hari akan menghadapi resiko politik yang tidak menyenangkan dari pemerintah. Tentunya, pada waktu itu terlihat adanya stigmatisasi terhadap UUD 1945, bahwa sebenarnya UUD 1945 telah membenarkan berbagai tindakan, yang sesungguhnya bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri. Ini baru hanyalah merupakan salah satu tantangan dan ujian yang sebelumnya dihadapi oleh UUD 1945 pada masa pemerintahan Orde Baru, selain ujian-ujian lainnya yang tentunya juga dilakukan oleh Orde Baru, yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Ujian itu misalnya, kekejaman politik; pengontrolan dan penghapusan pikiran-pikiran kritis dan perbedaan pendapat; dan humanisasi proses-proses bermasyarakat (Sutrisno,2009;119). Berbagai gagasan ilmiah yang mencoba untuk membongkar kedok dibalik keluarnya peraturan tentang perubahan UUD 1945, yang pada dasarnya peraturan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Tentunya hasilnya tidak akan berani untuk kemudian diungkapkan secara terang-terangan, apalagi yang kesimpulannya lebih lanjut mengarah pada perbedaan tafsir dengan apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, tentunya akan berhadapan langsung dengan penguasa tertinggi, yaitu Presiden. Paling tidak dapat dipastikan akan mendapatkan perlakuan politik yang bisa dibilang kurang begitu menyenangkan dari pemerintah, dengan berbagai cara yang kemudian dibuat- dibuatnya. Dalam hal ini menurut penulis, merupakan tindakan yang tentunya sangat bertentangan dengan jiwa UUD 1945 itu sendiri, yang di dalamnya secara tegas mengatur tentang kebebasan untuk mengemukakan pendapat, seperti dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945, walaupun sebenarnya peraturan tersebut masih perlu diatur kembali dalam undang-undang sebagai peraturan pelaksana yang berada di bawahnya. Mungkin dapatlah kemudian dikatakan bahwa maksud daripada dikeluarkannya berbagai peraturan hukum tersebut di atas, hanyalah bertujuan untuk mencegah dirubahnya UUD 1945, meminjam istilah Uno (2011;59) merupakan strategi politik (political strategy) daripada pemerintahan Orde Baru. Semua itu dilakukannya dengan tujuan utamanya adalah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
133
untuk tetap mempertahankan kekuasaannya agar nantinya tidak terjamah oleh yang namanya perubahan. Tentunya pemikiran tersebut, merupakan suatu ide yang dapat dikatakan adalah sifatnya konservatif dari Soeharto, kemudian dengan kedok yang sebelumnya dibuat-buat, berupa adanya propaganda untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, ada ketentuan inilah yang pada gilirannya membuat Pancasila menjadi ideologi yang bersifat beku dan tertutup, bukannya sebagai ideologi terbuka. Bahkan tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kekuasaan yang sebelumnya diberikan oleh UUD 1945. Kemudian dengan dalih palsunya untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, sebenarnya secara tidak langsung Orde Baru telah menjadikan Pancasila, sebagai pelindung terhadap kebencian rakyat terhadapnya. Pancasila juga pada waktu itu dijadikan asas tunggal dalam berorganisasi baik sosial maupun politik, yang sebenarnya merupakan tindakan Soeharto yang pada dasarnya hanya bertujuan untuk meredam adanya perbedaan politik, di mana sebelumnya bergejolak di masyarakat, yang mana perbedaan politik tersebut tentunya menurut Orde baru, merupakan salah satu penyebab dari tidak kondusifnya iklim politik di Indonesia, bahkan dapat saja membahayakan posisinya sebagai seoarang penguasa. Namun, patutlah kemudian disayangkan bahwa tujuan utama menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi sosial dan politik, tidak lain merupakan suatu alibi dibuat-buat untuk kemudian mengikat kebebasan rakyat dalam berorganisasi, terutama dengan tujuan untuk dapat menyampaikan pendapatnya, yang dalam kenyataannya tidaklah pula bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, Orde baru secara tidak langsung telah menjadikan Pancasila sebagai sebuah dongeng, yang selalu saja disebut-sebut dalam setiap pidato kenegaraannya. Kemudian pada akhirnya menyebabkan Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia menjadi kaku. Tentu implikasinya akan semakin menjauhkan Pancasila dari rakyat, karena ada pengertian bahwa hanya penguasalah yang merasa memiliki Pancasila dengan segala penafsirannya yang bersifat mutlak. Dengan demikian, Pancasila yang dianggap sebagai sebuah dongeng, maka terkait dengan hal tersebut, Surajiwo (2008;17) berpendapat bahwa orang yang beranggapan karena segala dongeng dan takhyul merupakan bagian tidak dapat diganggu gugat, maka dongeng dan tahayul itu pasti benar dan tidak boleh diganggu-gugat. Kejadian inilah yang mungkin dapat sedikit memberikan gambaran sebenarnya apa yang kemudian menjadi maksud daripada pemerintah, dengan menggunakan label Pancasila sebagai tameng daripada kelakuan buruknya, agar selanjutnya tidak melakukan perubahan terhadap UUD 1945, karena pastinya akan mengancam posisi penguasa. Dengan demikian pun berbagai argumentasi para ilmuwan yang sebelumnya dilakukan, terutama oleh pendukung-pendukung Orde Baru, dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
134
tujuan tidak lain agar rakyat nantinya lebih percaya, bahwa dengan merubah UUD 1945, berarti juga akan membubarkan NKRI. Mengenai adanya larangan perubahan terhadap UUD 1945, yang mana tentunya merupakan suatu propaganda yang pada dasarnya bersifat konservatif. Dapatlah kemudian dikutip pendapat dari Ahmadi (2007;203) bahwa propaganda konservatif yaitu propaganda yang bersifat status quo, ialah selalu mempertahankan apa yang ada, jangan sampai berubah. Sebab, dengan adanya perubahan terhadap UUD 1945, tentu pastinya akan mengancam kedudukan penguasa, yang mana pada dasarnya didukung oleh UUD 1945. Sedangkan di lain pihak dapat dikatakan bahwa UUD 1945 itu sendiri sebenarnya terlihat menunjukan watak yang benar-benar bersifat sentralistik. Kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, barulah kemudian datang setelah Orde Baru lengser dari kekuasaan secara tidak terhormat. Jatuhnya Soeharto secara dramatis pada 21 Mei 1998 melalui gerakan reformasi telah membuka peluang pada dua hal, pertama, terjadinya suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie, dan kedua, dinamisasi yang luas bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi total di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi total ini mengarah kepada pembaharuan struktural dalam bidang ekonomi, politik, hukum, moral, dan sosial budaya (Subekti,1998;11). reformasi total tentunya tidak mungkin dapat untuk dilaksanakan apabila dalam kenyataannya Orde Baru masih berkuasa. Dikarenakan dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki Orde Baru, tidak mungkin kemudian untuk dapat melakukan perubahan, apalagi berkaitan dengan adanya reformasi total yang sebelumnya dicanangkan. Bahkan karena siklus kekuasaan selama 32 tahun hanya berputar di sekitar Presiden Soeharto, UUD 1945 mengalami proses skralisasi luar biasa yang tidak boleh disentuh oleh perubahan sama sekali (Asshiddiqie,2005;83). Dapatlah dikatakan bahwa sebelumnya, istilah suatu perubahan merupakan kata, yang mungkin hanyalah sebuah mitos belaka, bahkan sangatlah jauh dari harapan untuk kemudian diwujudkan. Namun, untuk sekarang perubahan tersebut sudah menjadi suatu kenyataaan, mungkin dalam bahasa filsafatnya lebih tepat kemudian dikatakan bahwa UUD 1945 memang telah mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah (Bakhtiar,2008;23). Ini berarti terlihat bahwa dengan adanya perubahan terhadap UUD 1945, maka secara tidak langsung telah berhasil pula, membebaskan UUD 1945 dari kungkungan tafsir tunggal dari penguasa. Bahkan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk kemudian dapat memberikan pendapatnya, terkait dengan penafsiran terhadap UUD 1945, yang tentunya haruslah dilakukan secara ilmiah agar sesuai dengan jiwa UUD 1945.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
135
Dalam sejarahnya, momentum krisis ekonomi telah melahirkan berbagai gerakan, terutama dikalangan mahasiswa yang menuntut adanya reformasi total, dengan mengusung isue demokratisasi (Namira,2009;101). Datang krisis ekonomi banyak yang menduga daripada tidak berjalannya sistem politik yang demokratis, sehingga kemudian menghasilkan produk hukum elitis serta berwatak konservatif. Produk hukum yang sebelumnya dibuat hanyalah menguntungkan segelintir orang, menyebabkan orang yang sebenarnya mampu menjadi semakin mampu, sedangkan orang miskin menjadi bertambah miskin. Pendek kata bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam memeratakan pendapatan (income), merupakan penyebab utama pergolakan sosial untuk kemudian mengakhiri semua bentuk ekploitasi yang dilakukan negara terhadap rakyat. Krisis moneter yang melanda Asia kemudian menjadi momentum untuk menggusur pemerintahan Orde Baru. Harus diakui bahwa terlepas dari keberhasilannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Orde Baru telah gagal menciptakan sistem politik dan kehidupan bernegara yang demokratis (Kencana dan Azhari,2005;123). Memang di bawah pemerintahan Orde Baru Indonesia merupakan salah satu negara, yang kemudian bisa dibilang memiliki kedudukan terpandang di ASEAN, yang mana dikarenakan adanya kemajuan yang cukup pesat di bidang ekonominya. Bahkan, dapatlah dilihat daripada kemajuan ekonomi Indonesia yang pesat oleh karena dilaksanakannya atau diimplementasikan rencanarencananya dalam setiap gerak pembangunan. Namun, keberhasilan ekonomi yang telah dicapai oleh Orde Baru, yang selanjutnya dikuti dengan pembangunan sebegitu pesatnya, namun sangat disayangkan bahwa dalam kenyataannya tidak dapat dibarengi dengan keberhasilan untuk kemudian memberantas KKN. Bahkan dapatlah dikatakan bahwa semboyan pembangunan yang selalu saja digembar gemborkan oleh penguasa, hanyalah merupakan suatu ajang untuk kemudian mengeruk keuntungan dengan merugikan rakyat banyak. Karena pada akhirnya rakyatlah yang diharuskan menanggung beban besar, akibat dari utang yang sebelumnya dipinjam oleh pemerintah, kemudian untuk itu tentunya harus dilunasi kembali oleh negara tersebut. Keberhasilan pembangunan ekonomi malah dianggap sebagai peluang untuk melakukan KKN yang dilakukan oleh para anggota keluarga dan kroni para penguasa, baik dipusat maupun di daerah (Budiardjo,2008;133). Peritiwa seperti tersebut di atas itulah, yang kemudian menjadi penyebab memuncak dan akhirnya menjadi pemicu utama kemarahan rakyat, yang selama ini berhasil ditekan oleh penguasa, bahkan selanjutnya menyembunyikan di tempat yang dapat dikatakan tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun. Reaksi keras yang kemudian ditunjukan oleh rakyat, merupakan salah bentuk ketidakpuasaan rakyat selama ini terhadap jalannya pemerintahan yang sebelumnya dipimpin oleh Presiden Soeharto. Bahkan, pada waktu itu, timbulnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
136
tuntutan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden oleh rakyat yang sebelumnya dimotori oleh mahasiswa, bahkan disertai pula dengan terjadinya berbagai huru hara di berbagai daerah. Dalam situasi demikian, Jenderal Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI dan digantikan oleh B.J Habibie yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden (Abidin,2005;55). Dapatlah dikatakan bahwa sejak saat itulah Orde Reformasi dan babak baru perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai (Setiadi,2005;49). Memasuki pasca orde baru atau yang kemudian dikenal dengan sebutan era reformasi telah menuntut perubahan di semua sektor kehidupan (Uno,2011;37). Penyebab utamanya, dikarenakan oleh adanya berbagai kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan Orde Baru, telah berhasil mencemari berbagai sektor kehidupan dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari sektor ideologi sampai pada pendidikan yang untuk selanjutnya perlu dilakukan sebuah reformasi yang dapat dikatakan bersifat total. Menurut Salim (2009:3) bahwa tahun 1997 merupakan momentum awal dimulainya era reformasi di negara Republik Indonesia. Era reformasi menuntut perubahan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada tiga aspek yang menuntut perubahan yang lebih cepat, yaitu aspek politik, ekonomi, dan hukum. Bahkan dari ketiga sektor di atas, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan prioritas utama dan bersifat mendasar yang kemudian perlu segera untuk dibenahi. Hal tersebut dilakukan, disebabkan selama ini oleh Orde Baru telah melakukan rekayasa terhadap hukum guna mendukung serta mengokohkan kekuasaannya. Bahkan ketika itu, hukum tersebut dijadikan sebagai pembenar berbagai tindakan penguasa, yang pada hakekatnya merupakan bentuk penindasan terhadap rakyat. Hal ini dapat membuktikan bahwa hukum pada dasarnya memiliki fungsi yang sangat sentral, yaitu sebagai perekayasa masyarakat (social engineering), yang selanjutnya mengarahkan masyarakat ke arah apa yang sebelumnya menjadi tujuan utamanya. Namun, hanya saja pada waktu itu tujuan apa yang kemudian hendak dicapai, adalah sangat tergantung kepada kehendak daripada penguasa. Hukum hanyalah merupakan dasar legalitas belaka, terutama sebagai wujud utama pembenaran daripada pemerintah dalam melakukan berbagai tindakan, yang pada hakekatnya tidak dapat dibenarkan, jika kemudian dipandang dari sudut keadilan. Semua hal tersebut dilakukan, yang sebenarnya di dasari oleh pemikiran bahwa tanpa adanya legalitas, maka dapat dipastikan bahwa tindakan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintahan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan tidak sah. Berdasarkan pengalaman sejarah seperti tersebut di atas, tentunya kita telah belajar dari masa lalu, yang jika hanya menempatkan kedudukan hukum sebagai legalitas belaka, yang tentunya isi hukum tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan moralitas,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
137
menyebabkan hukum itu kemudian menjadi jauh dari cita-citanya yang dinginkan. Bahkan ada pepatah Yunani yang mengatakan bahwa Ouid leges sine moribus, apalah artinya hukum tanpa moral. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Muhtarom (2008;146) kemudian berpendapat bahwa reformasi di bidang hukum berusaha untuk menegakkan kembali supremasi hukum. Dikarenakan sebagai suatu negara hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan dasar dalam menjalani berbagai bentuk kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum kemudian didudukan pada posisi yang tertinggi, sehingga nantinya siapa saja yang telah melakukan tindakan apapun haruslah sebelumnya berdasar dan bersumber pada hukum. Namun, hukum sebagaimana dimaksudkan adalah hukum yang benar-benar telah meletakan prinsip keadilan di atas segala-galanya. Bahkan, jika terjadi pelanggaran hukum, baik oleh siapapun, tentunya harus ditindak dengan tegas tanpa kemudian melihat status sosial seseorang, apakah dia rakyat biasa maupun seorang pejabat. Permikiran ini didasari bahwa kedudukan setiap orang adalah sama di depan hukum, yang berarti tidaklah memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, pada dasarnya semuanya mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum (equlity before the law). Asas kesamaan dalam hukum merupakan salah satu bentuk dari supremasi hukum (supremacy of the law), dengan adanya supremasi hukum, tentunya diharapkan mampu untuk kemudian merubah sendi-sendi kehidupan yang lainnya, sehingga pada akhirnya dapat mengarahkan kepada keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam memandang perbedaan antara hukum yang sebelumnya berlaku pada era Orde Baru, dengan hukum yang kemudian berlaku setelah reformasi. Harusnya untuk itu, sesegera mungkin dilakukan berbagai perubahan yang sifatnya mendasar dan tak terelakan, untuk dapat memperbaiki kehidupan, dengan membersihkan sistem hukum yang sebelumnya telah tercemar oleh Orde Baru. Reformasi ini merupakan kesempatan kedua yang kemudian dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk melakukan pembenahan kembali, setelah gagalnya kesempatan pertama untuk melakukan perbaikan terhadap kehidupan bangsa setelah jatuhnya Soekarno pada masa Orde Lama. Usaha pertama yang dijalankan untuk selanjutnya dilakukan Indonesia adalah keberhasilannya dalam melakukan perubahan kehidupan yang sifatnya sangat mendasar, terutama terhadap tatanan dasar daripada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pada dasarnya, membawa pengaruh besar terutama terhadap aspek yang dapat dipandang dari sudut hukum tata negara. Bahkan Sinaga (2007;47) terkait dengan akibat daripada adanya perubahan terhadap UUD 1945 bahwa hal ini telah merubah tata
I Gusti Ngurah Santika, SPd
138
kehidupan politik, kepemerintahan dan kenegaraan di Indonesia. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 merupakan tindakan nyata sebagai upaya pembaharuan terhadap sistem pemerintahan negara sebagai program utama di era reformasi, bahkan reformasi dan pembaharuan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dikarenakan bahwa reformasi pengertian umumnya adalah pembaharuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reform bukan sekedar pembaharuan tetapi perubahan radikal untuk perbaikan di suatu masyarakat atau negara (Salle,2007;51). Dengan demikian, pada dasarnya reformasi bermaksud untuk merubah secara radikal terhadap tatanan dasar yang tidak adil pada masa Orde Baru melalui perbaikan terhadap praktik-praktik demokratis sebagai sebuah negara yang menganut demokrasi. Senada dengan pendapat tersebut, Tim Litbang HAM Depham RI (2005;2) berkaitan dengan jatuhnya Orde Baru yang merupakan era reformasi menyatakan bahwa era ini sebenarnya sebagai transisi dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan yang demokratis. Ini membuktikan bahwa sistem pemerintahan yang hanya dibangun dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang bersifat otoriter, tentunya tidak akan mampu untuk dapat bertahan lama. Bahkan, ada suatu pernyataan yang sebelumnya mengatakan bahwa bentuk kekuasaan paling menindas hanya merupakan suatu kekuasaan yang menunggu untuk kemudian dijatuhkan. Hal ini terbukti pada saat pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru yang menjalankan pemerintahan negara, dengan cara-cara yang dapat dipandang tidak demokratis serta mengarah menjadi absolute, pada akhirnya jatuh juga, bahkan bisa dibilang dengan cara yang tidak terhormat pula. Tidak lain bahwa bangsa Indonesia menginginkan suatu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang baru, demokratis, dengan menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi kedaulatan tertinggi (Setijo,2008;92). Selama ini kedaulatan rakyat telah dimanipulasi oleh penguasa, bahkan dengan marekayasa prosedur demokrasi, telah menyebabkan sang pemilik kedaulatan, dalam arti yang sebenarnya, ternyata tidak mampu untuk berbuat banyak dalam situasi seperti itu. Oleh karenanya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat kepada pemiliknya, dipandang perlu untuk kemudian dilakukan berbagai tindakan yang dianggap perlu dan harus dilakukan secepatnya, seperti mendesak Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Karena memang banyak yang berpendapat bahwa tersendatnya saluran kedaulatan rakyat, tidak lain disebabkan oleh dominannya peran Soeharto sebagai seorang Presiden yang juga ditentukan menganut sistem presidensial. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa pendukung utama dari dominannya kekuasaan Presiden Soeharto dalam percaturan politik di Indonesia selama ini, dikarenakan bahwa UUD 1945 itu sendiri bersifat sentralistik dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
139
instrumentalistik. Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan kemudian adalah dengan cara melengserkan Presiden Soeharto dari jabatannya, yang selanjutnya disusul dengan adanya reformasi total terhadap UUD 1945. Kemudian peristiwa yang pertama adalah dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, disebut sebagai era reformasi sebagai awal dari perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis dengan agenda utama untuk meletakan kedaulatan di tangan rakyat. Dengan kedaulatan berada di tangan rakyat diharapkan rakyat untuk ikut serta terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan agar kemudian tidak ada penyimpangan dari tujuan semula yang sebelumnya mendasari. Oleh karena itulah, Winardi (2008;45) kemudian menyatakan bahwa era reformasi memberi harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, tansparan dan memiliki akuntabilitas tinggi, serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpendapat. Untuk mencapai hal tersebut di atas, reformasi perlu didahului dengan melakukan perubahan terhadap sistem hukum, khususnya hukum tertinggi yaitu UUD 1945. UUD 1945 yang menjadi dasar dari segala hukum yang sebelumnya berlaku, tentu dapat dikatakan hanyalah merupakan suatu gerakan reformasi, yang merupakan bentuk euporia demokrasi di mana sifatnya hanyalah sesaat. Menurut Asshiddiqie (2005;6) bahwa gagasan perubahan UUD 1945 kembali muncul dalam perdebatan pemikiran ketatanegaraan dan menemukan momentumnya di era reformasi. Dengan demikian, era reformasi telah membuka keran yang lebih besar berupa kesempatan untuk kemudian melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yang tentunya tidak boleh dilewatkan momentumnya begitu saja. Meskipun pada awalnya sempat menimbulkan pro kontra, namun akhirnya UUD 1945 pun nantinya telah beberapa kali diamandemen (Maksudi,2012;99). Hal tersebut terjadi, tidak lain disebabkan oleh adanya berbagai pihak, yang masih berbeda pendapat maupun persepsi dalam memandang perubahan terhadap UUD 1945. Disatu pihak, ada yang kemudian memandang perlu, untuk dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 dengan sesegera mungkin. Dikarenakan dalam kenyataannya selama ini, UUD 1945 lah yang sebenarnya menyebabkan sistem pemerintahan berjalan menjadi tidak demokratis. Dilain pihak, ada yang sebelumnya memandang dengan bersikukuh untuk tetap mempertahankan UUD 1945, menurut mereka bahwa bukan UUD 1945 yang kemudian patut untuk disalahkan, melainkan orang yang sebelumnya kebetulan menduduki jabatan, yang sebenarnya telah melenceng dari apa yang kemudian seharusnya dijalankan, atau dengan kata lain pendapat ini menggantungkan kehendak daripada orang sebagai penyelenggara negara. Oleh karena
I Gusti Ngurah Santika, SPd
140
itulah, maka UUD 1945 tidaklah dipandang perlu untuk dirubah, lagipula di dalam UUD 1945 terdapat ideologi negara yang merupakan kekuatan pemersatu rakyat serta sebagai norma rujukan pemecahan masalah bangsa, yang tentunya jika berkehendak untuk merubahnya dapat dipastikan kemudian akan menimbulkan konflik politik yang berkepanjangan. Seperti apa yang sebelumnya terlihat dalam sejarah, terutama pada saat sidang-sidang Konstituante yang bertugas dalam membentuk sebuah UUD baru ternyata gagal. Kegagalan daripada Konstituante dikarenakan tidak tercapainya suatu kesepakatan berkaitan dengan ideologi negara yang sangat membahayakan keutuhan negara, kemudian baru berakhirnya ketika dibubarkan oleh Soekarno, yang semata-mata bberujuan untuk mengakhiri konflik ideologis yang tidak berkesudahan tersebut. Namun, akhirnya kedua belak pihak menemukan jalan keluarnya, berupa persetujuan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dengan berbagai jaminan, terutama jaminan terkait dengan perubahan yang akan dilakukan tidaklah termasuk Pembukaan UUD 1945, yang memang di dalamnya memuat Pancasila sebagai ideologi negara (rechtsidee). Jaminan tersebut kemudian dituangkan kembali dalam lima kesepakatan MPR, dimana lima kesepakatan tersebut merupakan pedoman dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Lagipula memang pada awalnya perubahan bukanlah dimaksudkan terhadap Pembukaan UUD 1945, melainkan hanyalah terhadap Batang Tubuh UUD 1945, yang sebenarnya menjadi penyebab utama pemegang kekuasaan eksekutif menjadi otoriter. Semua hal tersebut terjadi dikarenakan pasal-pasal yang ada di dalam Batang Tubuh UUD 1945 pada dasarnya sebagai pendukung utama terbentuknya konsep excutive heavy. Tabel 2.1 Perbandingan cara pemerintahan Orde Lama dengan Orde Baru
Perbandingan Cara Pemerintahan Orde Lama dengan Orde Baru No. 1. Orde Lama Pada era Soekarno tidak ada sistem kepartaian. Orde Baru Pada era Soeharto dalam praktik melahirkan sistem kepartaian yang hegemonik.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
141
2.
Tumpuan kekuatan Orde Soekarno sebagai Presiden.
Lama
adalah Tumpuan kekuatan Orde Baru adalah Presiden Soeharto, ABRI, Golkar dan Birokrasi.
3.
Jalan yang ditempuh era Orde Lama adalah Jalan yan ditempuh pada inkonstitusional. era Orde Baru adalah memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional. Obsesi utama Orde Lama adalah pemusatan kekuasaan dengan alasan, paling tidak yang dikemukakan secara terbuka, untuk mencegah disintegrasi. Sedangkan Orde Baru memiliki Obsesi membangun stabilitas nasional sebagai prasyarat kelancaran pembangunan ekonomi. Sumber: diolah dari Mahmud MD (2011; 308-309)
4.
6. Latar Belakang, Dasar Pemikiran Amandemen UUD 1945 Akhirnya kekuasaan yang hanya dipertahankan dengan kekuatan semata disertai dengan tekanan-tekanan yang cukup intensif, baik sifatnya tersembunyi maupun terbuka, tidak mungkin akan mampu untuk bertahan lama, kekuasaan dengan kekerasan hanyalah mungkin dapat dipertahankan untuk sementara waktu saja, yang mana kemudian hanya tinggal menunggu waktu untuk kemudian ditumbangkan oleh rakyat. Kemudian ketertindasan tersebut akan mencoba untuk terus mencari jalannya sendiri, terutama untuk melawan ketidakadilan yang kemudian pada akhirnya akan berhenti, hanya dengan hapusnya semua bentuk penindasan. Seperti apa yang pernah dilakukan sebelumnya oleh penguasa Orde Baru terhadap rakyatnya sendiri pada masa pemerintahannya. Jalan untuk mengakhiri ketertindasan tersebut, akhirnya terbuka dengan lebarnya yang dimulainya pergerakan oleh rakyat Indonesia, yang sebenarnya dimotori oleh mahasiswa telah membuka lebar-lebar keran reformasi, sehingga kedaualtan rakyat dapat mengalir kembali sampai kemudian ke hilirnya untuk selanjutnya dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan. Arus reformasi telah bergulir di Indonesia mulai tahun 1998 (Muntoha,2008;260, Ryacudu,2011;58). Dalam cerita sejarahnya, dapatlah kemudian ketahui bahwa peristiwa sebenarnya tentang pergerakan rakyat Indonesia untuk melawan penguasa Orde Baru yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
142
otoriter sudah dimulai sebelum tahun 1998. Hanya saja gerakan berupa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat tersebut tidak bersifat terbuka, karena sebelum dapat muncul kepermukaan saja, Orde Baru akan segera menumpas dengan mengambil tindakan yang dipandang sifatnya sangat represif. Bahkan, penguasa tidaklah segan-segan untuk segera memadamkan semua gerakan perlawanan yang sebelumnya dilakukan oleh para penentang Orde Baru, yang kemudian disiram dengan kekuatan bersenjata, sehingga sampai benarbenar padam serta tidak mungkin dapat untuk hidup kembali. Hal tersebut baru berakhir, dengan timbulnya arus reformasi yang merupakan manifestasi dari bentuk kekecewaan rakyat terhadap sistem pemerintahan Orde Baru, yang dapat dipandang sangatlah tidak demokratis sifatnya disertai dengan pengekangan terhadap kebebasan rakyat dalam mengekspresikan hak-hak asasinya, terutama dalam kebebasannya untuk kemudian mengemukakan pendapatnya di depan umum. Tuntutan demikian akhirnya berujung pada aksi yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa ke DPR (Surajiwo, 2010;34). Mungkin dapatlah dikatakan, bahwa dengan rasa ketidakpuasan yang mendalam terhadap jalannya pemerintahan Orde Baru selama ini, terutama dengan jalan melakukan berbagai bentuk penindasan terhadap rakyat. Telah menyebabkan sebagian besar rakyat Indonesia untuk tergerak hatinya, kemudian menentang ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi selama ini, dengan melakukan unjuk rasa sebagai bentuknya yang dimotori oleh mahasiswa dengan kesadarannya sebagai kaum intelektual serta tentunya paling menyadari akan hal tersebut di atas. Dengan besarnya jumlah mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, telah menyebabkan mereka sulit untuk diusir dari gedung MPR dan DPR, bahkan berhasil menduduki gedung MPR dan MPR yang menurut mereka merupakan stempel daripada Orde Baru. Terjadinya persitiwa tersebut, kemudian telah berhasil mendorong Ketua MPR/DPR Harmoko untuk mendukung gerakan mahasiswa yang meminta kepada Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Dengan adanya berbagai gerakan protes dalam bentuk unjuk rasa yang semakin meluas, bahkan tidak saja terjadi di Ibu Kota Negara, namun sampai kedaerah-daerah, yang dalam kenyataannya tidak saja menimbulkan kerusakan berupa harta dan benda, tetapi juga jatuhnya banyak korban jiwa. Kemudian Soeharto menyatakan kesetujuannya untuk memenuhi tuntutan rakyat dengan meninggalkan jabatannya sebagai seorang Presiden. Dengan demikian peristiwa berdarah tersebut, merupakan usaha perjuangan rakyat dan mahasiswa dengan penuh semangat, bahkan dengan mengorbankan jiwa dan raga, sehingga berujung pada jatuhnya Soeharto dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan jatuhnya Orde Baru dari tampuk kekuasaannya, Sinaga (2010;7) kemudian menyatakan bahwa sejarah baru telah dimulai. Tentu saja, sejarah sebagaimana dimaksudkan oleh Sinaga tersebut di atas adalah terkait
I Gusti Ngurah Santika, SPd
143
dengan sejarah ketatanegaraan. Dimana mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan yang sebelumnya berusaha untuk kemudian memenuhi tuntutan daripada rakyat dan mahasiswa, sekaligus telah menegaskan bahwa rakyat Indonesia secara tegas menolak bentuk sistem pemerintahan yang sifatnya otoriter. Oleh karena itu, Zuriah (2008;7) kemudian berpendapat bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjungjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pada awal mulanya di era reformasi, berkembang dan popular di masyarakat banyaknya mengenai tuntutan reformasi, yang terutama didesakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk mahasiswa sebagai pelopor bangsa yang berada digaris depan perjuangan reformasi. Adapun yang kemudian menjadi agenda utama daripada reformasi, bahkan merupakan tuntutan komponen bangsa Indonesia di era reformasi itu, yaitu sebagai berikut. a. Amandemen UUD 1945; b. Penghapusan Dwifungsi ABRI (ABRI kini TNI dan Polri tidak boleh lagi berpolitik dan menduduki atau menjadi anggota legislatif dan eksekutif, pokoknya tidak boleh menduduki jabatan sipil); c. Penegakan supremasi hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); d. Otonomi Daerah yang seluas-luasnya (Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah); dan e. Mewujudkan kehidupan demokrasi termasuk kebebasan pers (Atmadja, 2006;70, Santika,2012;4-5). Dari berbagai agenda reformasi yang menjadi tuntutan komponen bangsa tersebut di atas, adalah sangat menarik dengan adanya tuntutan untuk kemudian mengadakan perubahan terhadap UUD 1945, yang mana pada dasarnya merupakan hukum dasar Indonesia. Di mana selama ini tidak mungkin bisa disampaikan di depan umum, dikarenakan bisa saja terancam oleh kekuasaan pemerintah. Maka untuk sekarang, setelah jatuhnya Soeharto kemudian menjadi suatu wacana yang tidak mungkin dapat untuk ditunda-tunda kembali. Bahkan dapat dikatakan telah menjadi agenda yang utama, dalam rangka membangun demokratisasi terhadap kehidupan bangsa ini. Adanya tuntutan Perubahan UUD Tahun 1945, pada waktu era reformasi tersebut, merupakan suatu langkah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
144
serta terobosan yang sifatnya sangat mendasar. Karena dapat diketahui pada era sebelumnya tidaklah dikehendaki adanya suatu perubahan terhadap UUD Tahun 1945. Apa yang sebenarnya mendasari adanya tuntutan untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945, sehingga memang dipandang betul-betul perlu untuk kemudian diadakan suatu perubahan konstitusional, yaitu sebagai berikut. a. Memuat ketentuan-ketentuan yang memfokuskan kekuasaan pada lembaga eksekutif (executive heavy) yang dipimpin oleh Presiden. Selain sebagai kepala eksekutif secara praktis Presiden menjadi ketua lembaga legislatif karena jika presiden tidak mau menandatangani sebuah rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat berlaku. b. Memuat ketentuan-ketentuan yang berwayuh arti, multi tafsir (multi interpretable) yang karena sistemnya yang executive heavy itu maka penafsiran konstitusi yang harus diterima sebagai kebenaran adalah penafsiran yang dibuat atau dianut oleh Presiden. c. Terlalu banyak memberi atribusi kewenangan kepada lembaga-lembaga legislatif untuk mengatur hal-hal yang sangat penting dengan undang-undang tanpa adanya limitasi yang tegas di dalam UUD padahal Presiden sangat dominan dalam proses pembentukan undang-undang. Banyaknya atribusi kewenangan yang diolah di dalam sistem executive heavy inilah yang menyebabkan isi undang-undang lebih banyak didominasi oleh kehendak-kehendak Presiden secara terus menerus mengakumulasikan kekuasaannya. d. Terlalu percaya pada semangat orang sebagaimana dinyatakan sendiri dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Di dalam Penjelasan UUD tersebut dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar (Konstitusi tertulis) tidaklah terlalu penting sebab yang lebih penting adalah semangat penyelenggara negara, jika semangat penyelenggara negara baik maka negara akan baik. Pernyataan itu benar untuk sebagian, tetapi kurang benar untuk seluruhnya (Mahmud MD,2011;378379). Terkait dengan adanya Perubahan UUD 1945, menurut MPR (2011;9-12) yang kemudian menjadi dasar pemikiran yang sebenarnya melatarbelakangi dilakukan suatu
I Gusti Ngurah Santika, SPd
145
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain sebagai berikut. a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakanakan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dominan eksekutif (excutive heavy,) yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden. Pada diri Presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (chief excutive) yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogative (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu tertulis jelas dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara tertinggi di bawah Majelis. Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden) yang menyebabkan tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) dan berpotensi mendorong kekuasaan yang otoriter. c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasalpasal yang terlalu luwes sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Rumusan pasal itu dapat ditafsirkan lebih dari satu, yakni tafsir pertama bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih berkali-kali dan tafsir kedua adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh memangku jabatan maksimal dua kali dan sesudah itu tidak boleh dipilih kembali. Contoh lain adalah Pasal 6
I Gusti Ngurah Santika, SPd
146
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan penjelasan dan memberikan arti apakah yang dimaksud dengan orang Indonesia asli. Akibatnya rumusan itu membuka tafsiran beragam, antara lain, orang Indonesia asli adalah warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia atau warga negara Indonesia yang orang tuanya Indonesia. d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang. Hal itu menyebabkan pengaturan mengenai MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), HAM, dan pemerintah daerah disusun oleh kekuasaan Presiden dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang ke DPR. e. Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah.Hal itu membuka peluang bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain, sebagai berikut. 1. Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada Presiden. 2. Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat, kurang mempunyai kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 3. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses dan tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
147
4. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Kemudian ditambah adanya lagi alasan lainnya tentang perubahan UUD 1945, menurut Atmadja (2006;71) yang merupakan suatu alasan politis, bahwa UUD 1945 belumlah cukup memuat landasan bagi kehidupan politik yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Perlunya diadakan suatu perubahan terhadap UUD 1945 ternyata disampaikan kembali oleh Harun Kamil, selaku Ketua PAH III pada waktu itu, yang kemudian memberikan pandangannya berupa pendapat tentang UndangUndang Dasar 1945. Pada intinya ia menyatakan bahwa. Kita menyadari bahwa betapa pentingnya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini karena merupakan salah satu agenda reformasi, juga kita mengetahui latar belakang daripada keinginan untuk merubah ini adalah karena dianggap UndangUndang Dasar 1945 ini sementara juga terlalu heavy executive, jadi ada pengaturan tentang masalah-masalah lembaga-lembaga tertinggi negara dan banyak hal mengenai masalah HAM yang perlu diperluas yang membuat latar belakang dan tujuannya adalah bagaimana supaya nanti dapat terciptanya suatu sistem politik demokratis yang kuat dan memberikan kesempatan adanya kedaulatan rakyat dan wujud demokrasi dan juga supremasi hukum dan terselenggarakan pemerintahan yang baik, untuk mewujudkan cita-cita kita untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur (Sekjen MPR,1999;2) Kemudian lebih lanjut kita menelusuri sejarah pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, jelaslah ketentuan pasal 3 itu memberikan suatu tugas kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyusun suatu Undang-Undang Dasar baru karena Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu memangnya dimaksudkan suatu Undang-Undang Dasar yang sifatnya sementara (Hadjon,1987;5). Oleh karena itu, perlunya UUD 1945 untuk dirubah, hal mana adalah sesuai sekali dengan fakta sejarah tentang pernyataan Soekarno sebagai ketua PPKI pada saat itu, yang menyatakan bahwa: ...Undang-Undang Dasar yang buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
148
Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, UndangUndang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutie grondwet (Mahkamah Konstitusi Jilid I,2010;38). Penggalan pernyataan Soekarno tersebut acapkali digunakan sebagai dasar pembenaran, bahwa para Perumus UUD 1945 (the framers of 1945 Constitution) menyatakan UUD 1945 bersifat sementara (Soemantri,2006;74). Untuk lebih meyakinkan pernyataan tentang perlunya perubahan terhadap UUD 1945, maka dalam hal ini Machmmudin (2003;19) menyatakan bahwa pada UUD 1945 itu, para pendiri bangsa ini sebenarnya telah memprediksi pergantian zaman. Mereka menciptakan landasan dasar UUD 1945 itu agar bisa mengikuti pergantian jaman dengan mempersiapkan salah satu pasal dan ayat sedemikian rupa sehingga dapat sebagai sarana untuk menyesuaikan isi Undang-Undang Dasar tersebut dengan kebutuhan dan keadaan jaman. Dengan demikian, UUD 1945 dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman sehingga dapat menampung dinamika kehidupan bangsa yang berjalan dinamis. Dengan demikian, nampak sekali dalam konsep amandemen tersebut, bahwa usul amandemen itu sangat dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa terakhir (Rahardjo,2000;xvi). Namun, perlulah diingat kembali bahwa tidak semua yang tercantum di dalam UUD 1945 dikatakan kemudian sebagai penyebab jalannya pemerintahan menjadi tidak demokratis. Tetapi harus benar-benar dicermati dengan cara yang lebih saksama apakah yang sebenarnya menyebabkan tidak baiknya sistem pemerintahan selama ini yang dianut. Sehingga kemudian tidak sepenuhnya hanya dapat menyalahkan UUD 1945, dikarenakan di samping adanya kelemahan yang memang melekat padanya, ternyata UUD 1945 dapat berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga ia telah mampu membuktikan kelebihannya. Hal senada juga dinyatakan oleh Nasriyah (2007;118) yang mengakui tidak hanya adanya kelemahan yang melekat pada UUD 1945, tetapi juga mengakui kelebihan yang menyertainya berkaitan dengan apa saja yang kemudian diatur dalam UUD 1945. Berikut ini merupakan kutipan pernyataan lengkapnya. Tetapi harus diakui, bahwa di samping mempunyai kelemahan, UUD 1945 memuat ketentuan yang baik, karena itu wajar untuk dipertahankan seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara berdasarkan atas hukum, prinsip kesejahteraan sosial, prinsip penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
149
yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain didasari oleh berbagai pemikiran tersebut di atas yang memang menjadi latar belakang untuk perlunya UUD 1945 dirubah. Maka berikut ini, merupakan tujuan utama daripada dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila; 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminanan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi; 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan mengimbangi (cheks and balances) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman; 5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakan etika, moral dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera;
I Gusti Ngurah Santika, SPd
150
6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum; 7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecendrungannya untuk kurun waktu yang akan datang (MPR,2011;12-13). Perubahan terhadap UUD 1945 memang harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda lagi, agar momentum semangat reformasi yang membakar tidak padam oleh gerusan waktu yang kian lama semakin berlalu. Namun, untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 tentunya tidak dapat langsung dilakukan, hal mana dikarenakan bahwa sebelumnya, telah ada berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sebelumnya merupakan warisan daripada Orde Baru, yang berpeluang menjadi penghambat utama untuk dapat melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, maka dipandang perlu terlebih dahulu untuk mencabut beberapa ketentuan peraturan perundangan yang dulunya merupakan penghalang, untuk dapat dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Seperti adanya Tap MPR RI No. IV/MPR/1983 yang kemudian dicabut dengan Tap MPR RI No. VIII/MPR/1998, lalu disusul kemudian dengan adanya pencabutan terhadap UU No. 5 Tahun 1998 dengan kemudian diganti dengan UU No. 6 Tahun 1999. Setelah dilakukannya pembaharuan terhadap ketentuan yang sebelumnya menghalangi perubahan UUD 1945, maka terbukalah peluang kembali untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Sebenarnya, mau tidak mau haruslah diakui bahwa dalam perjalanannya UUD 1945 sebenarnya telah pula mengalami perubahan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung perubahan UUD 1945 sebagai dimaksudkan tersebut, adalah perubahan terhadap UUD 1945 yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan, tidak lama berselang setelah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menjadi konstitusi pertama bagi negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam perjalanan sejarah selama periode Orde Baru berkuasa, haruslah diakui kembali bahwa sebenarnya UUD 1945 secara langsung telah dirubah dengan berbagai bentuk peraturan tertulis yang notabene kedudukannya berada di bawah UUD 1945, sehingga bunyinya maupun maknanya menjadi berubah. Perubahan sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas, yaitu.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
151
1. Penambahan kriteria telah berusia 40 tahun bagi Presiden maupun Wakil Presiden dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengubah Pasal 6 UUD 1945; 2. Pengutamaan tata cara pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat dalam Ketetapan MPR No. 1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR mengubah Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak; 3. Penetapan wewenang MPR untuk memberhentikan Presiden dalam Ketetapan MPR No. 1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR mengubah Pasal 8 UUD 1945; 4. Penetapan untuk mengisi kekosongan hukum dalam UUD 1945 pengisian jabatan Wakil Presiden melalui Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan telah mengubah UUD 1945 dengan membuat ketentuan bahwa dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap, maka MPR mengadakan Sidang Istimewa Khusus untuk memilih dan mengangkat Wakil Presiden apabila Presiden dan/atau DPR memintanya (Pasal 4 ayat (1); 5. Pemasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang sebelumnya bernama Angkatan Kepolisian Republik Indonesia kedalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sebelumnya bernama Angkatan Perang Republik Indonesia telah mengubah Pasal 10 UUD 1945 (Alrasid dalam Chaidir,2007;74-75). Selain telah terjadinya perubahan terhadap 1945 sebagaimana dimaksudkan oleh Alrasid di atas, maka Arinanto menyatakan bahwa UUD 1945 memang telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain. 1. Kemunculan tugas dan wewenang khusus Presiden/Mandataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam Sidang Umum MPR 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1998 telah mengubah ketentuan-ketentuan tentang tugas dan wewenang Presiden dalam UUD 1945;
I Gusti Ngurah Santika, SPd
152
2. Keberadaan menteri-menteri yang tidak memimpinan departemen seperti Menteri Koordinator, Menteri Negara, dan Menteri Muda dalam beberapa Kabinet Pembangunan di masa Orde Baru telah mengubah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa para menteri memimpin departemen pemerintahan; 3. Kemunculan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 dan UU No. 5 Tahun 1985 telah mengubah Pasal 37 UUD 1945 tentang Tata Cara Perubahan UUD 1945; 4. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui Ketetapan MPR No. XIII/MPR/1998 telah mengubah Pasal 7 UUD 1945 (Chaidir,2007;75-76). Kemudian agenda reformasi telah mengkristal menjadi sebuah wacana yang harus segera diwujudkan dengan bentuk yang nyata, seperti perubahan terhadap UUD 1945. Dan akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama dari segenap komponen bangsa, yang kemudian tertuang secara tegas dalam lima kesepakatan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 oleh MPR sebagaimana dimaksudkan di bawah ini. Dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945, kemudian PAH I meneruskan hasil kesepakatan dasar terkait perubahan UUD 1945 yang sedang dilaksanakan berdasarkan Tap MPR RI No. IX/MPR/1999. Hal ini bermaksud untuk semakin mempermudah melakukan perubahan, namun tentunya harus tetap dalam bingkai-bingkai kesepakatan luhur, sehingga nantinya tidak melenceng dari tujuan semula yang pada dasarnya merupakan tuntutan yang sebelumnya mendasari perubahan UUD 1945. Lima kesepakatan dasar ini menjadi pedoman dalam melakukan pembahasan dan mengambil keputusan mengenai perubahan UUD 1945 di MPR (Asshiddiqie,2009;295). Berikut ini merupakan kesepakatan yang ditetapkan dalam melakukan perubahan yaitu. 1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial; 4. Akan memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal; 5. Melakukan perubahan dengan cara addendum (Mahkamah Konstitusi,2010 ;217218).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
153
Berikut ini merupakan penjelasan dari kesepakatan dasar MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945. Bahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan. 2. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang mejemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. 3. Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial bertujuan untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh NKRI dan pada tahun 1945 telah dipilih oleh para pendiri negara ini. 4. Kesepakatan lain adalah memasukan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh). Peniadaan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam menentukan status Penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bukan produk BPUPKI dan PPKI karena kedua lembaga itu menyusun rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal) UUD 1945. 5. Kesepakatan perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum. Artinya perubahan UUD 1945 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan UUD 1945 diletakan melekat pada naskah asli (MPR,2011;19-20). Sebelum memulai pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Panitia Ad Hoc III terlebih dahulu melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU), dengan beberapa pakar hukum tata negara. Pada saat rapat dengar pendapat umum tersebut, muncul dua pendapat pakar hukum tata negara. Disatu pihak ada
I Gusti Ngurah Santika, SPd
154
yang berpendapat bahwa sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu harus ditetapkan, sesuai dengan ketetentuan Pasal 3 UUD 1945. Pihak lain berpendapat bahwa UUD 1945 tidak perlu ditetapkan, tetapi langsung saja dilakukan perubahan terhadap UUD1945, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Berdasarkan diskusi di atas maka Panitia Ad Hoc III menyepakati untuk langsung mengadakan perubahan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, akhirnya MPR dalam sejarahnya telah berhasil melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali dalam suatu rangkaian perubahan konstitusional. Akhirnya, keberhasilan MPR dalam merubah UUD 1945 disertai hasil-hasil dari perubahan terhadap UUD 1945, yang waktu itu UUD 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen yang sebelumnya dilakukan sebanyak empat kali dalam satu rangkaian perubahan oleh MPR, sebagai lembaga berwenang untuk melakukan perubahan konstitusi. Menyusul setelah disahkannya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dapatlah dipandang telah tuntas. Mengingat perubahan dilakukan dengan cara addendum, maka perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakan melekat pada naskah asli. Sehingga, naskah resmi UUD 1945 adalah naskah yang terdiri atas lima bagian, yaitu: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (naskah asli); 2. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, perlu diketahui bahwa dalam perjalanan yang menyertai UUD 1945 setelah dilakukan amandemen sebanyak empat kali dalam suatu rangkain kesatuan perubahan,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
155
ternyata telah menimbulkan suatu polemik yang berkepanjangan. Polemik yang muncul disebabkan adanya semacam pendapat, yang pada intinya menyatakan bahwa perubahan yang selama ini dilakukan oleh MPR adalah tidak sah. Salah satu polemik yang kemudian muncul pada waktu itu, yaitu tentang penempatan UUD 1945 di dalam lembaran negara, yang sebelumnya memang tidak dilakukan setelah UUD 1945 diamandemen. Terlebih lagi dengan adanya suatu pernyataan berupa pendapat, bahwa dengan tidak adanya penempatan UUD 1945 di dalam lembaran negara, maka semua pemerintahan yang sebelum terbentuk setelah periode amandemen UUD 1945 adalah tidak sah, termasuk pula hasil pemilu tahun 2004, karena yang mendasarinya saja sudah tidak sah. Oleh karena itu, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan Ketua MA Bagir Manan dengan tegas, menyatakan bahwa: penempatan UUD di dalam Lembaran Negara hanyalah administratif, bukan imperatif. Ketua MA, Bagir Manan, menyatakan bahwa tak ada keharusan memasukan UUD di dalam Lembaran Negara karena ketentuan tentang Lembaran Negara itu diatur di dalam UU dan UU yang mengatur itu, yakni UU No. 2 Tahun 1950 sama sekali tak menentukan bahwa UUD harus masuk di dalam Lembaran Negara (Mahmud MD,2010;42). Lebih lanjut menurut Bagir manan bahwa UU tak boleh mengikat UUD karena UU lahir dari UUD; sebuah peraturan tak boleh mengikat ketentuan yang mengikat peraturan yang melahirkan atau menjadi induknya. Atau dengan kata lain, bahwa dapatlah dikatakan kedudukan UU berada di bawah UUD 1945 (lexs superior derogate legi inferiori). Dengan istilah yang sama, bahwa induk dari segala perundang-undangan ialah Undang-Undang Dasar (Pudjosewojo,2004;24). Bahkan Menurut Kusuma (2007;144) bahwa UUD 1945 setelah amandemen, sah karena diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis. Selain itu, amandemen adalah upaya untuk menyempurnakan UUD 1945 yang merupakan amanat dari pendiri negara. Untuk menghentikan polemik tersebut, maka pembentuk undang-undang pada akhirnya memerintahkan untuk kemudian memasukan UUD 1945 ke dalam lembaran negara. Masalah tersebut dapatlah kemudian dilihat dalam UU No.10 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) undang-undang tersebut. Pada dasarnya bunyi ketentuan undang-undang tersebut memerintahkan agar menempatkan UUD 1945 dalam lembaran negara, namun berarti bukan tanpa catatan, dikarenakan bahwa terkait dengan penempatan UUD 1945 dalam lembaran negara, bukanlah yang kemudian menentukan kekuatan berlakunya UUD 1945
I Gusti Ngurah Santika, SPd
156
tersebut, melainkan hanyalah bersifat konfirmasi saja. Pernyataan tersebut terpapar dengan jelas di dalam Penjelasan UU No. 10 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2011. Sehingga dengan demikian keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, bukanlah disebabkan oleh penempatannya dalam lembaran negara, sebagaimana dimaksudkan oleh mereka yang sebelumnya memandang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus ditempatkan dalam lembaran negara. Bahkan menurut penulis, mereka itu beranggapan sama, dengan menyamakan kedudukan Undang-Undang Dasar dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang notabene kedudukan undang-undang jelas-jelas berada di bawah UndangUdang Dasar 1945. Selain munculnya polemik sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, ternyata setelah dilaksanakannya perubahan terhadap UUD 1945, kemudian hasil dari amandemen tersebut telah menjadi putusan resmi dari MPR, akhirnya selanjutnya dapat dilaksanakan sebagai hukum dasar dalam ketatanegaraaan yang baru. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, muncul pula pro dan kontra terhadap hasil perubahan UUD 1945. Berikut ini merupakan reaksi terhadap perubahan UUD 1945 yang kemudian dapat dikatagorikan menjadi 3 arus, yaitu sebagai berikut. 1. Arus yang menghendaki agar Indonesia kembali saja ke UUD 1945 yang asli sebagaimana yang dibuat oleh founding people, sebab UUD 1945 merupakan karya agung para pendiri yang dibuat dengan penuh keiklasan; dalam arus ini bahkan muncul pendapat bahwa secara prosedural perubahan UUD 1945 itu tidak sah. 2. Arus yang menghendaki agar hasil amandemen sekarang dilaksanakan dulu dan tak perlu berburu-buru diperbaiki lagi sebab ia merupakan hasil maksimal yang telah menampung berbagai keinginan secara kompromistis. 3. Arus yang menghendaki dilakukan amandemen lanjutan agar perubahan itu menjadi semakin baik sebab yang ada sekarang dianggap masih menyisakan berbagai masalah yang harus diselesaikan (Mahmud MD,2010;xii). Bahkan ada pendapat yang menyatakan agar dilakukan perubahan UUD secara total dengan membuat UUD yang baru (Rindjin,2009;269). Walaupun terjadi pro dan kontra terhadap hasil perubahan UUD 1945 disatu pihak, namun Mahmud MD (2007;6) dipihak lain berpendapat dengan menunjukan secara jelas sisi positif dari hasil perubahan bahwa setelah UUD 1945 diubah tampak jelas kepada kita bahwa kehidupan demokrasi tumbuh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
157
semakin baik. Serta pernyataannya lainnya, yang menurut penulis merupakan pendapat paling menarik dari Mahmud MD (2007;3) yang dengan mengutip pendapat K.C Wheare untuk kemudian menghentikan pro dan kontra, terkait dengan hasil perubahan UUD 1945 bahwa yang penting prosedurnya benar dan demokratis, sebab kata K.C. Wheare konstitusi itu merupakan resultante atau kesepakatan-kesepakatan politik sesuai dengan situasi poleksosbud dan waktu tertentu. Jadi, dalam hal ini yang berlaku adalah apa yang telah dijadikan kesepakatan bersama, yang sebelumnya dilandasi dengan nilai-nilai luhur untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai bersama. Tentunya tanpa adanya suatu kesepakatan bersama, untuk kemudian mengambil suatu keputusan, maka hal itu hanyalah merupakan suatu angan-angan belaka yang dikehendaki untuk selanjutnya bisa diwujudkan. Untuk itu, diperlukanlah persetujuan bersama dalam bentuk penerimaan, disertai dengan gerak pelaksanaan UUD 1945, secara murni dan kesekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dari berbagai hal tersebut di atas, maka patutlah dikutip pendapat dari Ashhiddiqie (2006;xi) yang menyatakan bahwa: terlepas dari perbedaan-perbedaan pendapat yang demikian, naskah UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah berubah dan perubahannya itu sudah disahkan secara konstitusional. Oleh karena itu, sekarang bukan lagi saatnya untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Akan tetapi, sekarang adalah saatnya untuk melaksanakan segala ketentuan UUD 1945 pasca perubahan itu secara konsekuen. Mengutip singkat dari pendapat Sudargo Gautama (2005;28) yang menyatakan bahwa pilihan singkat hukum di waktu sekarang ini secara umum bukan merupakan soal lagi. tidak lain, dikarenakan dari berbagai pendapat yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh para ahli, maka penulis tentulah sangat setuju dengan pendapat-pendapat mereka tersebut di atas. Bahwa UUD 1945 memang telah dirubah dan tentunya perubahannya tersebut sudah sah, bahkan telah mengikat segenap komponen bangsa. Walaupun kemudian terjadi pro dan kontra yang mengiringinya, terutama terkait dengan hasil daripada Perubahan UUD 1945, tetapi hal itu merupakan gejala yang biasa terjadi dalam negara demokrasi. Karena terkait dengan permasalahan pengambilan keputusan apapun, pastinya ada pihak yang kemudian setuju ataupun tidak. Apalagi menyangkut persoalan konstitusi yang di dalamnya mengatur tidak hanya lembaga-lembaga negara, tetapi sekaligus juga mengatur seluruh elemen bangsa terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
158
bernegara. Untuk itu, dalam alam demokrasi seperti sekarang ini adalah wajar di mana setiap orang merasa untuk bebas dalam menyampaikan pandangannya, bahkan termasuk hasil perubahan daripada UUD 1945, baik dalam bentuk sikap yang sifatnya setuju maupun tidak setuju. Adanya kenyataan tersebut merupakan warna dalam demokrasi, yang dulunya mungkin belumlah mendapatkan tempat serta kesempatan yang sewajarnya, terutama untuk mempermasalahkan UUD 1945 di masa Orde Baru. Tetapi perlulah diingat kembali bahwa walaupun negara kita adalah sebuah negara yang sistem pemerintahan berbentuk demokrasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, tetapi masih perlulah dibatasi kemudian oleh hukum menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi anarkis terkait dengan masalah pandangan tentang arti sebuah kebenaran. Patutlah pula dirasakan adanya perbedaan antara UUD 1945 yang belum diamandemen dengan hasil perubahan terhadap UUD 1945. Di mana perubahan UUD 1945 telah membawa dampak yang cukup positif adalah merupakan sebuah fakta, walaupun tentunya masih ada kekurangan di sana-sini yang kemudian perlu diperbaiki kembali ke depannya. Untuk itu, sebelum adanya kesepakatan politik yang baru, tentang perubahan lanjutan terhadap UUD 1945 di masa yang akan datang, maka yang dipandang paling penting untuk sekarang, adalah dengan melaksanakan kesepakatan politik tersebut terlebih dahulu. Dengan demikian, tentu kita akan lebih fokus untuk melaksanakan UUD 1945 secara konsisten, bukannya hanya mempermasalahkannya terus menerus, sehingga hanya dapat hidup dalam tataran teoritis, bukannya dalam kenyataannya (praktis). Boleh saja, kemudian ada yang mempermasalahkan hasil dari amandemen UUD 1945, yang selanjutnya berjuang untuk berusaha memperjuangkan, sehingga nantinya dapat mengubahnya kembali UUD 1945, agar apa yang mungkin menurut mereka adalah terbaik, yang seharusnya dicantumkan dalam UUD 1945 menjadi sebuah kenyataan. Namun, perlulah penulis ingatkan kembali, bahwa perjuangan tersebut, haruslah tetap melalui jalur-jalur konstitusional yang memang telah disediakan (Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 37 UUD 1945). Bukannya dengan jalur yang pada dasarnya bertentangan dengan hukum yang berlaku, misalnya mencoba dengan upaya paksa untuk mengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik yang dilakukan melalui kekerasan, revolusi, maupun dengan dekrit seperti apa yang dilakukan oleh Soekarno tanggal 5 Juli 1959. Dengan terjadinya peristiwa seperti itu, pastinya kemudian akan menimbulkan gejolak, bahkan dapat mengalami goncangan ketatanegaraan yang dahsyat dalam waktu berkepanjangan. Revolusi hanya akan berhasil, jika sebelumnya ada dukungan yang datang, baik itu berupa dukungan politik maupun dukungan dari militer, yang selanjutnya akan memberikan legitimasi, terhadap tindakan-tindakan yang mungkin sebenarnya, jika kita lihat kembali
I Gusti Ngurah Santika, SPd
159
dari konstitusi sebelumnya, adalah merupakan tindakan yang tidak konstitusional. Namun, dengan berhasilnya revolusi yang kemudian disertai dengan pembentukan hukum baru, sehingga dari ilegal menurut hukum yang lama kemudian menjadi legal konstitusional dikarenakan berhasil ditegakan oleh penguasa, bahkan kemudian mendapatkan dukungan luas dari rakyat, sehingga revolusi tersebut kemudian menjadi legitimit.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
160
BAB III SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA A. Teori Pembagian Kekuasaan
Salah satu ciri untuk dapat disebut sebagai negara konstitusional (constitutional state), yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, selain juga dipersyaratkan adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan (distribution or separation of power). Yang tentunya kedua hal tersebut merupakan suatu masalah yang sangat prinsipil, terutama dalam rangka bertujuan untuk dapat membatasi kekuasaan penguasa yang dalam sejarahnya cenderung bersifat absolut. Teori pembatasan (limitation of power) sangatlah erat sekali kaitannya dengan teori tentang pemisahan kekuasaan (separation of power) ataupun dengan teori pembagian kekuasaan (division of power or distribution of power). Setiap orang yang telah dengan jelas mengetahui tentang teori pemisahan kekuasaan, tentunya sangat mengenal dengan akrab nama Montesquieu, yang merupakan filsuf Perancis pencetus doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan teori yang kemudian dinamakan dengan Trias Politika. Menyusul setelah lahirnya teori tersebut, kemudian menjadi buah perdebatan di berbagai belahan dunia, baik dalam bentuk diskusi baik langsung maupun secara tidak langsung yang menghiasi berbagai buku karya-karya dari para ahli, terutama yang bergerak di bidang ketatanegaraan. Tentunya sampai sekarang pun berkaitan dengan teori Trias Politika, ternyata masih banyak yang mendiskusikannya bahkan menjadi sebuah perdebatan hangat di seputar kenegaraan, baik dalam bentuk dukungan sepenuhnya terhadap gagasan tersebut, maupun yang kemudian tidak menyetujuinya, terutama terhadap gagasannya tentang adanya pemisahan mutlak terhadap kekuasaan (separation of power). Namun, setidaknya perlulah untuk diketahui oleh khalayak umum, bahwa sebelum Montesquieu mencetuskan teori Trias Politica-nya, ternyata ada seorang sarjana lainnya, yang sebenarnya merupakan penggagas utama tentang teori pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga negara. Tentunya lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan fungsi berbeda, yang kemudian berarti tugas dan fungsinya tersebut, hanyalah kemudian dapat dipegang oleh masing-masing lembaga-lembaga negara. Adalah John Locke yang merupakan seorang sarjana berkebangsaan Inggris, dalam tulisan terkenalnya yang berjudul Second Treaties of Civil Government (1690), dengan pendapatnya tersebut bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum, tidaklah boleh untuk dipegang sendiri oleh mereka yang bertugas untuk menerapkannya. Dengan kata lain, maksud daripada John
I Gusti Ngurah Santika, SPd
161
Locke adalah untuk membedakan tugas dan kewenangan dari badan legislatif dan eksekutif agar kemudian tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kemudian sampailah John Locke pada konsep pembagian kekuasaan negara, yang terdiri atas tiga fungsi, yaitu. a. Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan; b. Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan; c. Fungsi federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai (Busroh,2001;84) Menurut John Locke bahwa fungsi mengadili haruslah termasuk ke dalam lingkungan eksekutif, sedangkan urusan mengenai diplomasi atau hubungan luar negeri merupakan suatu badan tersendiri, yang tentu menurutnya harus terpisah dengan badan eksekutif. Dengan kata lain, Locke telah menyatukan fungsi antara lembaga ekskutif dan yudikatif, yang pada dasarnya merupakan dua lembaga negara yang memiliki kedudukan dan fungsi berbeda antara satu sama lainnya. Kemudian beberapa puluh tahun setelah itu, yaitu pada tahun 1748 filsuf Perancis yang bernama Montesquieu berinisiatif untuk mengembangkan lebih lanjut pemikiran cemerlang John Locke tentang pembagian kekuasaan, yang kemudian hasil pemikirannya tersebut dituangkan kembali dalam bukunya yang berjudul LEsprit des Lois (The Sprit of the Laws). Alasan utama lahirnya ide pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri sifat despostis daripada raja-raja Bourbon. Kemudian ia berkeinginan untuk menyusun suatu sistem pemerintahan di mana para warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Dalam bukunya The Spirit of Laws berkaitan dengan absolutnya kekuasaan pada waktu itu, karena memang tiadanya konsep pembagian kekuasaan yang cukup jelas, maka dengan pemikiran jernih dan mendalam terhadap ketiga kekuasaan tersebut, maka dipandang perlu untuk kemudian memisahkan kekuasaan secara tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif (Montesquieu,2011;187). Pendapat ini merupakan hasil dari suatu rangkaian kegiatan Montesquieu, terutama dalam mempelajari sistem ketatanegaraan dari berbagai negara yang selama ini memang dikunjunginya, terutama negara yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Inggris. Yang menurut Montesquieu benar-benar telah mempraktekan idenya dalam kenyataan. Menurutnya, bahwa sistem konstitusi Inggris telah menerapkan ide tersebut berupa prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, seperti apa yang Montesquieu bayangkan pada waktu itu. Meskipun doktrin ini sebenarnya tidaklah pernah berlaku di Inggris yang bersistem parlementer, tetapi ia tetaplah penting dalam alam ketatanegaraan Inggris.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
162
Berkaitan dengan tidak berlakunya teori pemisahan kekuasaan di Inggris, karena di sana justru konsep yang sebenarnya dianut adalah adanya hubungan yang erat sekali antara fungsi lembaga eksekutif dan legislatif. Terlihatlah secara jelas tentang pernyataan tersebut di atas, seperti adanya suatu persyaratan untuk dapat menduduki jabatan eksekutif, tentu harusnya juga duduk dalam lembaga legislatif. Dengan demikian, jelaslah bahwa apa yang telah dilaksanakan dalam sistem ketatanegaraan Inggris, sebenarnya tidak menganut konsep pemisahan kekuasaan secara mutlak, sebagaimana apa yang kemudian dibayangkan oleh Montesquieu. Karena terkait dengan ide pemisahan kekuasaan sebagaimana yang diinginkan oleh Montesquieu, memanglah tidak mungkin untuk sepenuhnya dapat diterapkan dalam praktik ketatanegaraan di sana. Terkait dengan adanya teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu, yang kemudian membagi kekuasaan tersebut, menjadi tiga cabang kekuasaan. Maka lebih lanjut menurutnya, bahwa ketiga kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lainnya, bahkan terkait dengan tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang nanti menyelenggarakannya. Namun, perlu untuk diketahui bahwa terkait dengan adanya pemisahan kekuasaan terutama berkaitan dengan ide awal mula kelahirannya, sebenarnya bukanlah berasal dari Montesquieu. Kemudian lebih lanjut yang memberikan nama dari ketiga teori pemisahan kekuasaan tersebut dengan nama Trias Politika, bukanlah Montesquieu melainkan Immanuel Kant. Bahkan, Ghoffar (2009;11) menyatakan dengan tegas bahwa dasar pemikiran Trias Politica sudah pernah dikemukakan oleh Aristoteles dan kemudian juga pernah dikembangkan oleh John Locke. Dengan begitu, konsep ini bukan ajaran yang dapat dikatakan baru bagi Montesquieu. Kemudian Latif (2009;24) lebih lanjut menyatakan hal yang kurang lebih sama bahwa terkait dengan ajaran ini, yang oleh Immanuel Kant disebut sebagai doktrin Trias Politica Montesquieu. Menurutnya bahwa dasar pemikiran doktrin Trias Politica sebelumnya pernah pula ditulis oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan kembali oleh John Locke, dengan menyatakan bahwa yang membatasi kekuasaan yang absolut, bukan karena pemisahan kekuasaan melainkan hak asasi manusia itu sendiri. Tidaklah jauh berbeda dengan pernyataan tersebut di atas, maka di bawah ini dapatlah kemudian dinyatakan, bahwa. Gagasan Trias Politika ini semula ditawarkan oleh John Locke dengan tawarannya tentang keharusan adanya tiga kekuasaan yang berbeda agar negara tidak menjadi totaliter, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Kemudian oleh Montesquieu menyempurnakannya dengan meletakan kekuasaan federatif sebagai bagian dari eksekutif, serta meletakan kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri sejajar
I Gusti Ngurah Santika, SPd
163
dengan kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Nama Trias Politika itu bukan berasal dari John Locke maupun Montesquieu, melainkan berasal dari Immanuel Kant yang datang kemudian (Mahmud MD dan Marbun,2000). Ajaran Trias Politica Montesquieu, sangatlah menekankan kepada kebebasan kekuasaan yudikatif (kehakiman), hal ini dikarenakan menurutnya bahwa di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu, untuk dijamin bahkan menjadi taruhan. Tidak lain, karena Montesquieu tahu betul bahwa jika seandainya kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dengan kedua lembaga negara lainnya, maka apa yang mungkin saja dapat terjadi, adalah berupa putusan-putusan pengadilan tidaklah dapatlah dipertanggungjawabkan, terutama terhadap kebenaran dan keadilan. Bahkan, yang menjadi jaminan utama dalam mempertahankan hak asasi manusia merupakan tugas mulia daripada lembaga yudikatif. Latar belakang pemisahan lembaga yudikatif dengan kedua lembaga lainnya tersebut, tidak lain karena dilatar belakangi daripada pekerjaan Montesquieu itu sendiri sebagai seorang hakim, yang memang tahu betul apa yang seharusnya menjadi tugas dari lembaga yudikatif, yang mana tentunya sangat berlainan sekali dengan lembaga negara lainnya, terutama berkaitan dengan kedudukan, wewenang, fungsi dan tugasnya sehari-hari. Kekuasaan legislatif, menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kemudian kekuasaan eksekutif meliputi pelaksanaan daripada undang-undang, (tetapi oleh Montesquieu juga termasuk dalam tindakan di bidang politik luar negeri), sedangkan lembaga terakhir yang terkait dengan kekuasaan yudikatif adalah kewenangan untuk mengadili atas terjadinya suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Dari sini kemudian dapatlah kita membedakan antara konsep teori dari John Locke dengan Montesquieu. Jika Locke memasukan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, maka untuk Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang pada dasarnya berdiri sendiri. Hal mana disebabkan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang hakim, Montesquieu mengetahui betul bahwa kekuasaan eksekutif itu sangat berlainan sekali dengan kekuasaan yudikatif. Sebaliknya, Montesquieu cenderung untuk memasukan kekuasaan federatif ke dalam kekuasaan eksekutif (Budiardjo,2008). Oleh karena itu, berkaitan dengan kekuasaan yudikatif, maka Bechar (2005;99) berpendapat dengan menyatakan bahwa yang khusus itu (kekuasaan yudikatif, pen) berbeda dengan kewajiban pokok pejabat-pejabat eksekutif maupun legislatif yang berpangkal kepada pembagian kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan menurut Trias Politika Montesquieu. Tidak lain terkait dengan kewenangan lembaga yudikatif, yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
164
memiliki kekuasaan berbeda dan sangat besar, terutama dalam memutuskan sebuah kasus konkret berdasarkan norma umum, yang tentunya harus selalu dapat dipertahankan independensinya dari pengaruh-pengaruh lembaga-lembaga negara lainnya, yang pada hakekatnya berada di luar kekuasaan yudikatif. Untuk itulah, perlunya pertimbangan yang matang, bahwa terkait dengan ketiga kekuasaan, yaitu berkenaaan kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, untuk selanjutnya tidak saling mencampuri urusan satu sama lainnya. Tidak lain hanya semata-mata demi menjaga independensi daripada masingmasing lembaga negara, serta yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk menjamin hak asasi manusia agar nantinya benar-benar tidak dilanggar oleh penguasa, yang ketika itu kebetulan memegang kekuasaan tersebut. Menurut pendapat dari Montesquieu, bahwa jika ketiga kekuasaan dan tiga badan kenegaraan tersebut tidak sekali-kali dipisahkan, maka dengan sendirinya para penguasa di dalam negara tersebut dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. (Utrecht,1986;19-20). Dan kemudian dapatlah dibayangkan, jika seandainya ketiga kekuasaan tersebut, hanya diletakan dalam satu lembaga negara, yang tentunya akan berpotensi untuk menggoda penguasa, yang kebetulan pada waktu itu memegang kekuasaan tersebut, untuk kemudian menyalahgunakannya yang pada akhirnya hanya melanggar hak-hak asasi manusia, padahal seharusnya perlu dijamin. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka tidaklah mungkin dapat untuk ketiga kekuasaan tersebut kemudian diserahkan hanya kepada satu tangan ataupun satu lembaga saja. Untuk itu, ketiga kekuasaan tersebut haruslah diserahkan pula kepada ketiga lembaga negara, yang nantinya sudah ditentukan masing-masing hanya memiliki satu kewenangan saja, yang berarti akan berbeda kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Hal tersebut dikarenakan oleh ide Montesquieu yang mengemukakan ajaran Trias Politika pada dasarnya bertujuan, hanya untuk memberantas atau setidak-tidaknya diharapkan nantinya dapat membatasi kekuasaan penguasa (raja) yang pada waktu itu bersifat absolut dan bertindak secara sewenang-wenang, agar hak kebebasan serta kemerdekaan individu (para warga negara) dapat terjamin pelaksanaannya (Soehino,1984;5). Penguasa yang memiliki kekuasaan terbatas, terutama dalam melakukan tindakan serta mencegah kemungkinan menjadi absolutnya kekuasaan penguasa, yang tentunya bertujuan agar kemudian dapat menjamin hak warga negara, merupakan landasan dari teori pemisahan kekuasaan ini. Hal ini merupakan suatu upaya dari Montesquieu dalam menjamin bahwa kewenangan yang kemudian diberikan kepada lembaga tersebut tidaklah disalahgunakan. Tujuan pembagian kekuasaan ini, adalah untuk mencegah adanya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
165
penyalahgunaan atau penyelewengan tersebut, maka kekuasaan itu harus dibatasi, antara lain dengan tidak memperbolehkan kekuasaan itu berada di satu tangan (Manan dan Magnar,1997;38). Jadi, kesepakatan yang didapatkan untuk sementara waktu ini, adalah kekuasaan tidaklah dapat diserahkan hanya kepada satu lembaga, terutama berkaitan dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara. Namun untuk itu, perlulah dipisahkan sedemikian rupa, agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang pada dasarnya tidak diinginkan seperti absolutnya kekuasaan penguasa. Menurut konsep semula, tujuannya ialah pemisahan kekuasaan guna mencegah keabsolutan penguasa. Karena itu kekuasaan harus dipisah (tanpa hubungan) satu sama lain (Kantaprawira,1990;52). Menurut beliau, kekuasaan itu bukannya hanya harus dibedakan saja, melainkan kita seharusnya memisahkannya juga, artinya membagi-bagi atas beberapa orang atau badan, karena penyatuan kekuasaan tersebut dalam satu tangan akan memusnahkan kemerdekaan rakyat (Apeldoorn,2011;302). Maka, jaminan utama kemerdekaan akan dapat tercapai, hanya jika ketiga kekuasaan tersebut benar-benar didistribusikan ke dalam beberapa lembaga negara, yang memang terpisah guna melaksanakan tugasnya masing-masing, yang mana tentunya berbeda serta secara terpisah dengan tujuan utamanya adalah untuk membatasi kekuasaannya, sehingga menjadi tidak absolut. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa gagasan pembatasan dan pengawasan penggunaan kekuasaan menjadi penting (Saptaningrum,2006;104). Yaitu dengan cara masing-masing kegiatan (fungsi, pen) tersebut adalah 1(satu) task (1985;22). Bahkan yang lebih ekstrim lagi menurut pendapat dari Montesquieu yang dengan tegas menyatakan, bahwa kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak ada kemerdekaan. Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusankeputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan individu-individu (Budiardjo,2008;282). Tentunya dalam hal ini akan sesuai dengan pandapat yang sebelumnya dikemukakan oleh Prodjodikoro (1981;64) yang menyatakan apabila kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu orang atau badan, maka tidak akan ada kemerdekaan (liberty), karena ada kekhawatiran di antara para anggota masyarakat, bahwa seorang (monarch) atau satu badan yang berkuasa itu akan membikin peraturan-peraturan yang kejam dan sekali akan melaksanakan peraturan-peraturan itu secara kejam.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
166
Kekuasaan pemerintahan yang terpusat hanya pada satu tangan cenderung disalahgunakan dan untuk mencegahnya harus dipisah-pisahkan (Pamudji,1983;24). Bahkan kecendrungan penyalagunaan kekuasaan yang akan berpotensi melanggar hak-hak dasar manusia, di mana sebenarnya merupakan jaminan utama, bahwa hanya dengan hak dasar tersebut, maka barulah kemudian ia dapat diakui sebagai seorang manusia dalam arti sesungguhnya, yang tentunya jika dilekati dengan hak-hak asasinya. Oleh karenanya, jaminan hak asasi manusia hanya dapat diperoleh, hanya dengan cara mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, yaitu dengan membagi-bagi atau memisahkan kekuasaannya, seperti apa yang sesuai dengan bunyi dari teori Montesquieu. Pokoknya menurut Montesquieu bahwa kekuasaan di antara ketiganya benar-benar harus dipisahkan satu sama lain, bahkan pemisahan ketiga kekuasaan tersebut haruslah bersifat mutlak. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa inilah sebagai awal mula dari adanya gagasan konstitusionalisme, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu dengan memisahkan ketiga kekuasaan tersebut serta mendistribusikan ke dalam tangan-tangan yang berbeda. Patutlah dicatat kemudian, bahwa biarpun pelajaran Montesquieu diterima dihampir semua negara-negara di Eropa Barat, ternyata hanya sebagian sajalah dari pelajaran tersebut, kemudian menjadi dasar dari tata negara. Karena apa yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Montesquie itu, tidaklah seratus persen benar-benar dapat diikuti oleh negara-negara lain. Dikarenakan jika tiga kekuasaan tersebut sungguh-sungguh dipisahkan secara mutlak, maka justru dapat menyebabkan kekuasaan masing-masing lembaga negara tersebut, tidaklah dapat diawasi yang kemudian akan berujung tidak terkendali kekuasaan yang ada pada lembaga tersebut. Hal tersebut dikatakan bahwa dengan tidak adanya pengawasan terhadap kewenangan dari badan-badan tersebut dalam menyelenggarakan kekuasaannya, sehingga akan menyebabkan pula si pemegang kekuasaan menjadi absolut. Namun, dapatlah dikatakan berkaitan dengan pembagian kekuasaan ini, merupakan konsep yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah ketatanegaraan bahkan masih tetap berlaku sampai sekarang. Terkait dengan pembagian kekuasaan, kemudian lebih lanjut menurut Marice Duverger dalam Thaib (1994;8) menyatakan bahwa persoalan tersebut maha penting. Oleh karena masalah tersebut dikemukakan justru pada waktu ilmu pengetahuan serta praktek ketatanegaraan meletakan pada tangan penguasa suatu maha kekuasaan yang tak dikenal oleh penindas manapun juga di dalam sejarah ketatanegaraan. Dalam suatu negara modern ternyata teori Montesquieu seluruhnya tidaklah kemudian dapat dipraktekan, terutama secara murni dan konsekuen, karena dalam kenyataannya pada
I Gusti Ngurah Santika, SPd
167
zaman seperti sekarang ini, rupanya teori Montesquieu seluruhnya hanya mungkin dapat dipraktekan di Amerika Serikat saja. Hal ini dikarenakan, menurut Dahl (1985;103) bahwa norma konstitusional memberikan suatu pembagian wewenang yang ekstensif berdasarkan federalisme dan pemisahan kekuasaan. Bahkan tidak lain dikarenakan bahwa berkaitan dengan pembagian kekuasaan berdasarkan Trias Politika dimaksudkan untuk lebih membatasi kekuasaan pemerintah federal terutama dalam hubungannya dengan badan legislatif dan badan yudikatif (Budiardjo,2008;278). Sehingga konsep utama yang menjadi dasar dalam hal ini adalah adanya suatu jaminan yang sifatnya utama terhadap hak asasi manusia yang kemudian ditentukan secara tegas oleh konstitusi. Ini dapat dimengerti, apabila kita mengingat, bahwa foundhing fathers dari Amerika sangat dipengaruhi oleh teori-teori Locke, Paine, Rosseau dan Montesquieu, yang sebelum Revolusi Perancis makin lama, makin besar pengaruhnya (Hartono,1982;25). Jadi para penyusun konstitusi Amerika Serikat, sangatlah mengagumi teori dari Montesquieu, yang memisahkan kekuasaankekuasaan ke dalam tiga lembaga negara. Selain alasan itu pula, kebencian penduduk koloni terhadap kekejaman kerajaan Inggris merupakan sebab utama, yang menjadi pemikiran penting dan mendasar bagi para penyusun konstitusi Amerika Serikat, untuk serta merta memisahkan kekuasaan ketiga lembaga negara tersebut dengan fungsinya masing-masing. Tetapi di situpun telah timbul kesukaran-kesukaran berkaitan dengan praktik ketatanegaraan, karena untuk zaman modern seperti sekarang ini, tidaklah mungkin untuk dapat diselenggarakan semua teori Montesquieu secara murni dan konsekuen dengan berbagai implikasi yang mengiringinya. Apalagi suatu negara yang pada dasarnya menganut asas negara hukum dalam arti luas, yang tentunya tidak mungkin membagi kekuasaan hanya satu tugas saja kepada satu badan untuk diselenggarakan, melainkan demi efisiensi dapat saja kemudian satu organ memiliki lebih dari satu kekuasaan. Namun, janganlah sampai nantinya demi efisiensi, dalam kenyataannya terjadi pelanggaran terhadap batasan-batasan hukum oleh suatu kekuasaan yang tidak jelas konsepnya. Terkait dengan hal tersebut di atas, Kelsen (2011;382) kemudian menyatakan bahwa demi keberhasilan kerja dari sistem ini, orang-orang yang diserahi kekuasaan dalam masing-masing bidang tidak diperbolehkan melanggar batas-batas kekuasaan yang ditetapkan untuk bidang-bidang lain, dan masing-masing bidang harus dibatasi, oleh hukum yang dibuatnya sendiri, pada pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan yang sesuai dengan bidangnya sendiri dan bukan bidang bidang lain. Jadi, pada garis besarnya Kelsen berpendirian bahwa keberhasilan suatu lembaga telah ditentukan secara tegas dalam aturan hukum yang membatasi masing-masing tugasnya. Yang kemudian tugasnya tersebut haruslah terlebih dahulu diselesaikannya sendiri, dikarenakan bahwa hanya dengan satu tugas tentunya fokus pekerjaannya akan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
168
lebih mudah diselesaikan, serta tidak diperbolehkan untuk ikut terlibat mencampuri urusan lembaga lainnya. Tidak lain dikarenakan sudah ditentukan batas-batas kekuasaan masingmasing, yang mana tidaklah boleh saling mencampuri urusan lembaga lain, semata-mata untuk menghindari terjadi tumpang tindih. Namun, tetap saja diperlukan upaya yang baik untuk dapat menyelesaikan suatu tugas, apalagi jika tugas-tugas sebagaimana dimaksudkan merupakan tugas yang sangat berat. Tentunya diperlukan suatu bantuan dari yang lembaga lainnya, sehingga dengan kebersamaan diharapkan suatu pekerjaan akan lebih mudah dapat diselesaikan. Bahkan, konsep ini sudah lama dipraktikan dan tidak dapat dihindari dalam praktik ketatanegaraan di semua negara yang kemudian dikenal dengan nama checks and balances. Amerika Serikat yang semula ingin menjalankan teori Trias Politika secara murni, kenyataan di dalam praktiknya saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan antara kekuasaan-kekuasaan lembaga-lembaga negara (checks and balance system). Sistem check and balance tersebut dimaksudkan agar ketiga badan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing dijalankan oleh Presiden, Kongres dan Mahkamah Agung) itu tidak menjalankan kekuasaannya melebihi atau kurang dari masingmasing kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi (Maksudi,2012;94-95). Asumsi yang digunakan oleh penyusun konstitusi Amerika Serikat, adalah menurut teori dari Montesquieu yang menyatakan, bahwa lebih terjamin dengan adanya pembagian fungsi yang berbeda pada lembaga-lembaga pemerintahan yang terpisah (di Amerika Serikat: Konggres, Eksekutif, dan Pengadilan) (Morgenthau,1990). Hal yang sama juga dinyatakan oleh K.C Wheare (2005;39) bahwa pada dasarnya kesimpulan-kesimpulan ini benar, tetapi ada satu hal yang harus digaris bawahi. Konstitusi Amerika memisahkan tiga institusi Kongres, Presiden (beserta seluruh stafnya), dan yudikatif dan tidak memperbolehkan terjadinya tumpang tindih personel di antara ketiganya, tetapi konstitusi tidak memberikan masing-masing proses itu kepada salah satu dari lembaga-lembaga tersebut dengan pemisahan secara mutlak. Morgenthau (1990;10) berpendapat bahwa para penyusunnya menyadari bahwa pemerintah yang bertindak adalah kekuasaan. Mereka mengadu ambisi, kepentingan dan kekuatan manusia di dalam ketiga departemen, yang satu dengan lainnya sedemikian rupa hingga suatu badan-badan dicegah mengambil semua kekuasaan, menjadi sangat kuat sehingga membahayakan. Namun, dilain pihak menurut Kusnardi dan Sarigih (1986;31) yang menyatakan sebenarnya jaminan bagi kebebasan politik tidak terlalu terikat kepada pemisahan kekuasaan seperti diterangkan di atas, akan tetapi bisa juga jaminan kebebasan politik itu diperoleh dengan menambahkan banyaknya badan-badan untuk tugas yang sama, sehingga perimbangan kekuatan bisa terwujud. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga usur tersebut
I Gusti Ngurah Santika, SPd
169
bukan hanya memungkinkan adanya checks and balances, tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Dwiyanto,2005;18). Kesemua organ yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pada umumnya akan selalu terdapat dalam setiap konstitusi. Paling tidak keberadaan fungsinya, merupakan pencerminan dari pentingnya organ-organ tersebut dalam setiap negara. Fungsi-fungsi antara organ yang satu dengan organ lainnya, adalah saling menjaga dan membatasi, sebagai wujud daripada keseimbangan kekuasaan, sehingga nantinya mampu mencegahnya menjadi absolut. Menurut apa yang diakui bahwa konstitusi yang diciptakan sebagai instrumen pengawasan dan perimbangan (checks and balances). setiap cabang pemerintahan bertugas mengawasi yang lain-lainnya, dan mempertahankan sikap seimbang secara keseluruhan. Cabang legislatifnya harus mengimbangi cabang eksekutif dan cabang yudikatif kedua-keduanya (Morgenthau,1990;9). Dengan demikian, kekuasaan tidaklah harus dipisahkan secara mutlak, namun demi keefektifan dan efisiensi untuk mencapai tujuan negara, maka kekuasaan perlulah kemudian dibagi dengan catatan tetap adanya hubungan satu fungsi dengan fungsi yang lainnya. Menurut Fadjar (2005;61) bahwa asas pembagian kekuasaan negara merupakan asas yang paling esensial pula bagi suatu negara hukum, karena selain berfungsi untuk membatasi kekuasaan dari penguasa (alat kelengkapan negara), juga untuk mewujudkan spesialisasi fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan zaman yang makin modern. Namun, dapatlah dinyatakan bahwa berkaitan dengan teori Montesquieu tentang adanya konsep berupa pemisahan ketiga kekuasaan tersebut, yang menurut Dwidjowijoto (2004;100) merupakan suatu prinsip untuk kemudian menjadi salah satu prinsip dasar penyelenggaraan negara melalui politik demokratis. Bahkan Strong (2005;14) menyatakan bahwa negara-negara yang ada di dunia dibedakan berdasarkan pada variasi komposisi dan hubungan di antara ketiga kekuasaan pemerintahan tersebut. Misalnya, jika hubungan antara lembaga negara antara yang satu dengan lainnya tidak ada hubungan berkaitan dengan tugas dan fungsinya, maka sistem pemerintahannya dapat disebut dengan Presidensiil. Sedangkan apabila antara kekuasaan lembaga negara eksekutif dengan lembaga negara legislatif ada hubungan, berupa saling mengawasi dan mengimbangi, maka sistem pemerintahan yang kemudian dianut adalah parlementer. Jadi, dalam pelaksanaan berupa praktik ketatanegaraan sepanjang sejarah, maka teori Trias Politika Montesquieu, tidaklah mungkin untuk dapat diterapkan secara murni dalam negara-negara modern seperti sekarang ini, yang pada dasarnya memiliki tugas-tugas kenegaraan kian hari menjadi semakin kompleks saja. Hal sama dinyatakan oleh Mahmud
I Gusti Ngurah Santika, SPd
170
MD dan Marbun (2000;14) dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa ajaran Trias Politika tidak pernah dapat dilaksanakan dengan konsekuen di negaranegara modern. Bahkan doktrin pemisahan kekuasaan, seperti apa yang kemudian dibayangkan oleh Montesquieu itu, dianggap oleh para ahli sebagai suatu pandangan yang tidak realistis, bahkan tentunya masih sangat jauh dari kenyataan. Pandangannya itu dianggap, oleh para ahli merupakan suatu kekeliruan utama Montesquieu, dalam usahannya untuk memahami daripada sistem ketatanegaraan Inggris yang sebelumnya dijadikan sebagai objek telaah, untuk selanjutnya mencapai kesimpulan mengenai Trias Politica itu, di dalam bukunya yang berjudul LEspirit des Lois (1748). Karena seperti yang telah dinyatakan sebelumnya di atas, bahwa sistem ketatanegaraan Inggris tidaklah menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan adanya hubungan yang sangat erat antara dua fungsi lembaga negara yang dipegang oleh eksekutif dan legislatif. Bahkan, dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang sungguh-sungguh mencerminkan gambaran seperti apa yang sebelumnya dibayangkan oleh Montesquieu, tentang konsep pemisahan kekuasaan (separation of power). Bahkan, struktur dan sistem ketatanegaran yang dijadikan objek dalam meyelesaikan bukunya itupun ternyata tidaklah menganut sistem pemisahan kekuasaan, seperti apa yang beliau bayangkan selama ini. Dalam hal ini Soehino (1983;219) berpendapat bahwa tentang ajaran Trias Politika Montesquieu kiranya hanya mungkin dapat dilaksanakan secara konsekuen pada negara hukum dalam pengertian sempit, seperti yang pernah dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Fichte, yaitu negara di mana tugasnya itu hanya membuat serta mempertahankan hukum. Lebih lanjut menurut Utrecht (1986;20) dengan adanya pemisahan mutlak seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak (dapat) ditempatkan di bawah pengawasan (controle) (suatu badan kenegaraan lainnya). Tidak ada pengawasan itu berarti kemungkinan bagi suatu badan kenegaraan untuk melampaui batas kekuasaannya dan oleh sebab itu kerja sama antara masing-masing badan kenegaraan dipersulit. Jadi, pemisahan kekuasaan secara mutlak seperti apa yang telah dikemukakan dahulu oleh Montesquieu, yang tujuan utamanya adalah untuk memberantas kekuasaan mutlak serta tindakan sewenang-wenang dari raja, tetapi malahan hanya mengakibatkan pemindahan saja sifat mutlak itu dari raja kepada tiap-tiap badan yang memegang kekuasaan tersebut, sebab badan-badan tersebut satu sama lain lalu tidak dapat saling mengawasi. Jadi akibatnya, sekarang yang dapat bertindak sewenang-wenang bukanlah raja melainkan badan-badan kenegaraan tersebut (Soehino,1983;217). Namun, untuk sekarang adalah lebih realistis jika ketiga kekuasaan tersebut tidak dipisahkan secara kaku, apalagi untuk negara yang menganut konsep pemerintahan demokrasi. Demikian juga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
171
menurut Murhani (2008;4) bahwa di dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang konsep dasarnya adalah pemisahan kekuasaan (separation of power) yang kemudian berkembang menjadi konsep pembagian kekuasaan (distribution of power). Jadi, kemudian hanya lembaganya saja yang mungkin dapat dipisahkan, namun berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh badan-badan tersebut satu sama lainnya, haruslah saling memiliki hubungan dekat. Sehingga dengan demikian, mungkin akan dapat untuk saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antar satu lembaga negara yang memiliki fungsi tertentu dengan lembaga lainnya yang tentunya juga memiliki fungsi berbeda. Hal ini dikarenakan menurut Isra (2010;75) bahwa perkembangan teori hukum tata negara modern (modern constitutional theory) membuktikan, cabang-cabang kekuasaan negara semakin berkembang dan pola hubungannya pun semakin complicated. Namun, jika selanjutnya kita sejenak kembali ke belakang, bahwa sebenarnya ajaran pembagian kekuasaan negara dari John Locke pada abad ke XVII baru merupakan gambaran dari suatu asas pokok dalam ajaran Montesquieu dalam abad ke XVIII, dalam bentuknya yang lain, yaitu menjadi kekuasaan pemisahan kekuasaan negara, dengan kemerdekaan politik sebagai tujuannya (Soehino,1983;118). Penulis rasa, bahwa tentang adanya pembagian kekuasaan, tentunya sangat berkaitan erat terutama dengan struktur ketatanegaraan dari suatu negara. Maka dalam hal ini menurut penulis, paling tidak, untuk pembagian struktur ketatanegaraan dapatlah kemudian dibagi menjadi dua bagian, yang tentunya memiliki sedikit persamaan dengan konsep pembagian kekuasaan dari Montesquieu. Kemudian dapatlah merujuk pada pendapat Soemantri (1981;39) yang menyatakan bahwa pada umumnya struktur ketatanegaraan suatu negara meliputi dua suasana, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang dimaksud dengan suprastruktur politik di sini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut alat-alat perlengkapan negara termasuk segala hal yang berhubungan dengannya. Mungkin untuk lebih memperjelas pengertian dengan apa yang dimaksudkan oleh suprastruktur politik adalah, seperti apa yang dimaksudkan oleh Soemantri tersebut di atas, adalah sama dengan maksud daripada pembagian ketiga kekuasaan dari Montesquieu, yang terdiri dari atas kekuasan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lebih lanjut terkait dengan infrastruktur politik disini adalah struktur politik yang berada di bawah permukaan. Adapun infrastruktur politik ini meliputi lima macam komponen, yaitu komponen partai politik, komponen golongan kepentingan, komponen alat komunikasi politik, komponen golongan penekan dan komponen tokoh politik (Soemantri,1981;39). Bahkan, kedua komponen tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya, sehingga keberadaannya tidaklah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
172
mungkin untuk dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena infrastruktur merupakan penggerak utama dari suprastruktur yang posisinya berada di atasnya. Selain adanya pembagian kekuasaan, seperti apa yang telah dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, ternyata ada sarjana lain yang juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan pembagian kekuasaan. Namun, dapatlah dikatakan bahwa pada esensinya ajaran pembagian kekuasaan sarjana ini, merupakan suatu konsep yang pada dasarnya sama, dengan apa sebelumnya disampaikan oleh para ahli di atas. Hanya saja perbedaan yang ada merupakan suatu rincian daripada konsep pembagian kekuasaan di atas, sehingga ada yang memperluasnya kembali sehingga kelihatan lebih banyak lembaga dan fungsinya, namun dapatlah dikatakan bahwa cakupan tugasnya adalah sama, dalam arti dapatlah kualifikasikan kembali ke dalam satu lembaga negara. Salah satu sarjana tersebut adalah C.V Vollen Hoven yang dapat dikatakan masih memakai cara berpikir menurut ajaran Montesquieu, akan tetapi kemudian memisahkan badan/kekuasaan Kepolisian secara khusus, sehingga menimbulkan suatu ajaran Catur Praja dari Van Vollen Hoeven (Muslimin,1980;8), ajarannya sebagaimana dimaksud, yaitu: a. Pemerintahan dalam arti sempit (bestuur), b. Polisi (Politie), c. Peradilan (rechtspraak), d. Membuat peraturan (regeling, wetgeving) (Soekanto dan Purbacaraka, 1993;57). Van Vollenhoven sendiri merupakan ahli hukum berkebangsaan Belanda yang merupakan pendasar daripada hukum adat. Kemudian ia berhasil merumuskan sistem hukum adat di Indonesia, kemudian membedakan antara susunan persekutuan-persekutuan hukum di berbagai daerah di kepulauan Indonesia menjadi 19 daerah hukum (Soepomo,2003;6,60). Dengan demikian dapatlah kemudian beliau disebut sebagai bapak dari hukum adat. Selain pembagian kekuasaan menurut Van Vollenhoeven, Good Now yang merupakan sarjana Amerika mengemukakan fungsi negara ada 2 bagian, yaitu. a. Policy Making; b. Policy Exsecuting (Prakoso,1988;2).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
173
Karena mengemukakan fungsi negara itu atas dua bagian, ajarannya itu terkenal pula sebagai Dwipraja (dichotomy). Policy making adalah kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat, sedangkan Policy exsecuting, adalah kebijaksanaan yang harus dilaksanakan oleh negara, untuk tercapainya policy making (Winarno,2009;40). Jadi, dapatlah kemudian dikatakan bahwa prasyarat untuk tercapainya policy making, harus dilaksanakan terlebih dahulu policy eksekuting, tanpa itu, tidak mungkin akan mencapai sasaran-sasaran yang menjadi tujuan policy making. Orang yang menetapkan policy making disebut dengan policy makers dan yang menetapkan policy exsecuting adalah eksekutor. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa policy makers adalah orang yang menentukan kebijaksanaan negara, tujuan-tujuan kenegaraan pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat. Atau menentukan tujuan mana yang baik untuk negara pada waktu tertentu. Jadi, semua kebijaksanaan suatu negara akan sangat terikat oleh waktu dan tempat di mana kebijaksanaan tersebut diambil dan akan dilaksanakan. Hal mana akan memerlukan suatu dasar daripada keberlakuan suatu kebijakan negara, seperti politis, yuridis, filosofis dan sosiologis. Bahkan, secara sosiologis kembali lagi di bagi menjadi dua dasar keberlakuan, yaitu keberlakuan yang dikarenakan kebijakan tersebut memang diakui berguna oleh masyarakat (Anerkennungstheory), namun apabila masyarakat tidak menaati kebijakan tersebut, penguasa dalam hal ini dapat kemudian memaksakannya dengan kekuasaan (machtstheory) yang dimilikinya, sehingga akhirnya masyarakat mematuhi kebijakan tersebut, terlepas diakui atau tidak oleh masyarakat itu sendiri terkait dengan manfaat daripada kebijakan tersebut (lihat Mertokusumo,1996;81). Policy exsecutors, adalah orang-orang yang berusaha untuk mencapai apa-apa yang telah diputuskan oleh policy makers atau menentukan daya upaya, alat-alat apa dan sebagainya untuk mencapai tujuan tadi. Ajaran dari Goodnow merupakan suatu reaksi terhadap suatu ajaran cara penggantian orang dalam pemerintahan. Ajaran ini terkenal dengan nama spoil system dari Andrew Jackson, di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa apabila suatu pemerintahan berganti, maka semua pegawai diganti oleh penguasa yang baru tersebut, dengan tujuan untuk kelancaran jalannya pemerintahan, tanpa adanya hambatan dari mereka yang tidak sepaham. Namun, Goodnow melihat fungsi negara itu secara prinsipil sehingga seperti diuraikan di atas mengutarakan dua fungsi negara. menurut Goodnow terhadap policy makers boleh dilaksanakan sistem Andrew Jackson. Sedang untuk policy excecutor tidak perlu dipakai, tetapi yang dijalankan adalah berdasarkan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
174
keahlian. Ajaran Goodnow ini disebut juga merit system, karena mengutamakan kegunaannya (Kusnardi dan Sarigih,2008;224). Keseluruhan fungsi negara tersebut di atas, pada dasarnya diselenggarakan oleh pemerintahan tentunya untuk mencapai tujuan daripada negara yang memang telah ditetapkan bersama. Adapun tujuan negara, tentunya akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Tidak lain hal ini disebabkan oleh berbagai perbedaan, baik dalam bidang ideologi terutama cita-cita yang kemudian memang diharapkan oleh masyarakat di suatu negara tertentu. Berikut ini merupakan pandangan dari para ahli tentang tujuan negara yang harus dicapai, yaitu antara lain. 1. Roger. H. Soltau. Tujuan negara menurut Soltau ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (the frees possible devolepment and creative self expression of it members) (Budiardjo,2008;55). 2. Harol.J. Laski Tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (Winarno,2009;41). 3. Plato Tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial (ibid). 4. Thomas Aquino dan Agustinus Untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat hanya kepada dan di bawah pimpinan tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan tuhan yang diberikan kepadanya (ibid). 5. Shang Yang Tujuan negara ialah membentuk kekuasaan. Untuk pembentukan kekuasaan ini ia mengadakan perbedaan tajam antara negara dengan rakyat. Perbedaan ini diartikan sebagai perlawanan atau kebalikan satu terhadap yang lainnya. Shang Yang mengatakan kalau ingin membuat negara kuat dan berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
175
sebaliknya jika orang hendak membuat rakyat kuat dan makmur, maka ia harus menjadikan negaranya lemah (Huda,2010;54-55). Dengan demikian, apa yang kemudian menjadi tujuan negara oleh Shang Yang adalah mempertentangkan antara rakyat dengan negara itu sendiri. 6. Dante Dante mempunyai cita-cita tentang tujuan negara bahwa seluruh negara-negara di dunia itu menjadi satu kekuasaan raja. Tujuan yang dimaksud Dante tidak untuk memperoleh kekuasaan yang mutlak, tetapi dengan mempersatukan semua negara-negara di bawah satu kekuasaan untuk membawa kemajuan umat manusia di seluruh dunia terutama dalam mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya (Kusnardi dan Sarigih,2008;76). B. Pengertian Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Istilah atau terminologi sistem ketatanegaraan, terdiri atas dua kata yaitu sistem dan ketatanegaraan. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan (Kencana dan Azhary,2005;4). Sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sanjaya,2010) Selain pengertian sistem menurut pendapat tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Sedangkan, Kaelan memberikan pengertian sistem yaitu suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa ciri-ciri dari sebuah sistem adalah sebagai berikut. a. Suatu kesatuan bagian-bagian ; b. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri; c. Saling berhubungan dan saling ketergantungan;
I Gusti Ngurah Santika, SPd
176
d. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem); e. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Kaelan,2008;57-58). Berdasarkan pengertian yang diberikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem memiliki karakteristik, Pertama, sistem pasti memiliki tujuanKedua, sistem selalu mengandung suatu prosesKetiga, kegiatan dalam suatu sistem selalu melibatkan dan memanfaatkan berbagai komponen atau unsur-unsur tertentu (Sanjaya,2011;49-50). Kemudian lebih lanjut menurut Maksudi (2012;8), dengan cara memberikan pengertian tentang sistem, yaitu: Sistem adalah sekumpulan objek (objectives) (unsur-unsur atau bagian-bagian) yang berbeda-beda (diverse) yang saling berhubungan (interrelated), saling bekerja sama (jointly) dan saling mempengaruhi (independently) satu sama lain serta terikat pada rencana (planned) yang sama untuk mencapai tujuan (output) tertentu dalam lingkungan (environment) yang kompleks. Oleh karena itu, untuk mengenal dan memahami suatu sistem perlu dikenali dan dipahami semua komponen yang terkandung di dalamnya (Hamalik,2010;135). Tidak lain dikarenakan bahwa masing-masing komponen tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain (Rusman,2012;1). Lebih lanjut menurut Maksudi bahwa untuk mengetahui apakah sesuatu itu dapat dikatakan sistem, maka harus mencakup lima unsur utama, yaitu. 1. Adanya sekumpulan objek (objectives) (unsur-unsur, atau bagian-bagian, atau elemen-elemen). 2. Adanya interaksi atau hubungan (interrealatedness) antar unsur-unsur (bagianbagian, elemen-elemen). 3. Adanya sesuatu yang mengikat unsur-unsur (working independtly and jointly) (bagian-bagian, elemen-elemen saling tergantung dan bekerja sama) tersebut menjadi suatu kesatuan (unity). 4. Berada dalam suatu lingkungan (environment) yang komplek (complex). 5. Terdapat tujuan bersama (output), sebagai hasil akhir (Maksudi,2012;8-9).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
177
Apabila kemudian pengertian sistem dikaitkan kembali dengan maksudkan untuk memperoleh pengertian dari sistem ketatanegaraan. Maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ketatanegaraan diartikan sebagai susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik yang menyangkut tentang susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara maupun yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama lain (Yuhana,2009;67). Dalam hubungannya dengan sistem ketatanegaraan, menurut Mahmud MD dalam Ghoffar (2011;48), yang terlihat dengan pendapatnya yang ternyata hampir menyamakan antara sistem ketatanegaraan dengan pengertian sistem pemerintahan, yaitu secara sederhana Mahfud MD mengatakan bahwa cara bekerja dan berhubungan ketiga poros kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial dapat disebut sebagai sistem pemerintahan negara. Sehingga yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian sistem pemerintahan yang diberikan oleh Mahmud MD sebagaimana dikutip kembali oleh Ghoffur, merupakan pengertian dari sistem pemerintahan dalam arti luas, yang tentunya dalam hal ini memiliki sedikit kemiripan dengan pengertian sistem ketatanegaraan sebagaimana dimaksudkan oleh Yuhana. Yang dalam kenyataannya kedua pengertian terkait dengan sistem ketatanegaraan tersebut, sama-sama menyangkut hubungan daripada lembaga-lembaga negara, terutama antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem dalam hal ini diartikan secara sempit sebagai mekanisme berdasarkan suatu tata aturan. Antara tata aturan dengan kelembagaan sesungguhnya merupakan suatu kesatuan, karena kelembagaan dapat didefinisikan sebagai suatu struktur aturan yang diformalisasi dalam seperangkat produk hukum (Asshiddiqie,2009;251) Selanjutnya jika pengertian sistem ketatanegaraan kemudian dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka dapatlah diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan Indonesia, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan organisasi negara Republik Indonesia, baik yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang maupun hubungannya satu sama lain menurut UUD 1945. Pengertian sistem ketatanegaraan yang kedua tersebut, atau hanya menyangkut Indonesia, mungkin dapatlah disamakan dengan pengertian Ius Constitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu pada saat tertentu (Dirdjosiworo,2003;163-164). Karena, pengertian tersebut menunjuk pada suatu ketatanegaraan tertentu, yaitu Indonesia, yang kemudian bisa juga disebut dengan nama
I Gusti Ngurah Santika, SPd
178
hukum tatanegara positif. Berbeda dengan pengertian yang kedua, maka pengertian sistem ketatanegaraan pertama dapat dikatakan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara, yang belum pasti berlaku dalam negara tersebut, namun bisa saja sudah berlaku di negara lainnya, seperti Ius Costituendum adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara tetapi belum merupakan kaidah (Dirdjosiworo,2003;164). Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa sistem ketatanegaraan negara lain tersebut, belumlah diadopsi ke dalam suatu negara yang sebelumnya mendambakannya. Dan apabila kemudian nantinya suatu sistem ketatanegaraan lain ternyata telah diikuti pula oleh suatu negara yang menginginkannya, selanjutnya berangsur-angsur menerapkannya di negara yang mendambakan tersebut, maka menjadilah hukum tatanegara positif yang tentunya akan berlaku di negara tersebut. Yang keberlakuan aturan tersebut tentunya akan mengikat dan memaksa, untuk kemudian diterapkan secara murni dan konsekuen dalam praktek ketatanegaraan, di negara yang memang telah mengadopsinya sebagai hukum tatanegara positif. Begitupun selanjutnya dengan definisi dari Chaidir (2007;72), yang menyatakan bahwa hukum tata negara positif merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku disuatu negara pada waktu tertentu. Pembedaan ini diperlukan karena ada juga hukum yang berlaku pada masa lampau dan hukum yang baru akan berlaku pada masa mendatang. Untuk sistem ketatanegaraan di Indonesia yang tentunya hanya berkenaan dengan lembaga-lembaga negara yang ditentukan dalam UUD, hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dalam arti sempit. Adapun jika dimaksud juga dengan lembaga negara di luar UUD, hal ini berkenaan dengan sistem ketatanegaraan dalam arti luas (Triwulan dan Widodo,2011;61). Hal ini disebabkan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, tidaklah dapat menampung pengaturan semua lembaga negara yang ada, karena di samping itu proses kehidupan bernegara berjalan secara dinamis. Sehingga mungkin saja pada saat UUD 1945 dibentuk ataupun di amandemen, belumlah terpikirkan atau diperlukan lembaga tersebut untuk kemudian dibentuk. Namun, dalam perkembangan kehidupan ketatanegaraan negara tersebut, kemudian ternyata dalam perjalanannya, adanya sebuah kebutuhan yang mendesak terkait dengan pembentukan lembaga negara tidaklah dapat dihindari, maka diperlukan jalan keluar yang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan cara mengatur keberadaan kelembagaan negara yang baru tersebut di luar UUD 1945, seperti dalam bentuk undang-undang ataupun dalam bentuk peraturan lain. Namun, tidaklah berarti bahwa lembaga negara yang dibentuk di luar UUD 1945, yang berarti tidak ditentukan secara tegas dalam UUD 1945, kemudian
I Gusti Ngurah Santika, SPd
179
dianggap sebagai lembaga negara yang kedudukannya berada di bawah lembaga-lembaga negara, yang telah ditentukan untuk dibentuk berdasarkan UUD 1945. Karena bisa saja, lembaga negara yang dibentuk kemudian tersebut merupakan suatu lembaga yang ditentukan bebas dan mandiri dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya. Dengan demikian, tentunya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lembaga ini memiliki kedudukan dan fungsi, yang pada dasarnya sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Tidak lain karena lembaga ini memiliki arti penting secara konstitusional (constitutional important), hal mana sebenarnya sangatlah tergantung daripada fungsi dan wewenang yang diembankan kepada lembaga tersebut, terkait dengan eksistensinya dalam ketatanegaraan Indonesia. Berkaitan dengan UUD 1945 yang merupakan sumber hukum ketatanegaraan Indonesia, sebelum diadakannya amandemen terhadap UUD 1945, lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalamnya adalah MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK , dan MA. Dengan catatan bahwa MPR merupakan lembaga yang sebelumnya mendapatkan kedudukan sangat istimewa di bandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya dalam UUD 1945. Dikarenakan MPT telah ditentukan sebagai pemegang kedaulatan rakyat, sehingga secara otomatis kedudukan lembaga negara lainnya kemudian berada di bawah MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 diamandemen oleh MPR sendiri, maka kedudukan MPR tidaklah lagi istimewa seperti dulunya, dimana ketika itu ditentukan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dikarenakan pada dasarnya kedaulatan rakyat telah dikembalikan kepada pemilik kedaulatan yang sesungguhnya, yakni melalui jalur konstitusi. Dengan demikian, adanya perubahan terhadap UUD 1945 terkait kedudukan MPR tentunya berakibat pula terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antar lembaga negara yang ada (Asshiddiqie,2009;v). Dengan perubahan konstitusi tersebut, banyak hal-hal baru yang sebelumnya memang belumlah dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kemudian berhasil diadopsi untuk ditetapkan menjadi ketentuan dalam UUD 1945. Bahkan, jika kita kembali melihat dengan cara saksama, akan terlihatlah banyak pula perbedaan baik antara isi UUD 1945 sebelum diamandemen dengan UUD 1945 sesudah diamandemen. Apalagi jika, kemudian membandingkan dari salah sudut lainnya, misalnya dengan membandingkan antara sistem ketatanegaraan negara lain, dengan yang dianut oleh Indonesia, tentunya sudah dapat dipastikan akan berbeda pula. Oleh karena itu, sistem ketatanegaraan republik Indonesia,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
180
menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, sama sekali tidak mengikuti ketatanegaraan lain (Joeniarto,1996;38). Bagan 2.1 Struktur Sistem Ketatanegaraan Sebelum Amandemen UUD 1945
Sementara itu, menurut hasil perubahan terhadap UUD 1945 setelah dirubah sebanyak empat kali dalam satu rangkaian perubahan. Maka berimplikasi pula terhadap perubahan lembaga-lembaga negara baik mengenai kedudukan, tugas dan fungsinya. Dengan demikian, lembaga-lembaga yang sekarang terdapat dalam UUD 1945 setelah dilakukan amandemen, yaitu sebagai berikut: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 2. Presiden dan Wakil Presiden; 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 5. Mahkamah Agung (MA); 6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 7. Mahkamah Konstitusi (MK), dan; 8. Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga negara dimaksudkan inilah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (main state function, principal state functions), sehingga lembaga-lembaga negara ini pula yang dapat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
181
disebut sebagai lembaga negara utama (main state organs, principal state organs atau main state institution) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip checks and balances (Triwulan dan Widodo,2011;61). Berikut ini, merupakan bagan yang mungkin dapat menunjukan adanya perubahan terhadap kedudukan lembaga-lembaga negara, yang memang telah ditentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, yang sebelumnya dilakukan sebanyak empat kali dalam suatu rangkaian perubahan oleh MPR. Yang tentunya perubahan tersebut telah mengakibatkan pula perubahan yang mendasar, terhadap mekanisme dalah hubungannya antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian, diharapkanlah bahwa bagan di bawah ini akan dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan struktur ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Haruslah diingat bahwa struktur kelembagaan negara yang sekarang dianut oleh UUD 1945 pasca amandemen tidaklah bersifat hierarkis vertikal dalam hubungannya antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Tidak lain hal ini dikarenakan bahwa setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dengan kedudukan lembaga negara lainnya dengan konsep yang kemudian menyertainya, yaitu adanya saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antara lembaga negara tersebut. Bagan 2.2 Struktur Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen 1945
I Gusti Ngurah Santika, SPd
182
Berbeda dengan sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945, maka UUD 1945 hasil perubahan tidak mengenal lagi istilah lembaga tertinggi negara, karena lembaga-lembaga negara tersebut, mempunyai kedudukan yang seimbang antara satu lembaga negara dengan lainnya, bahkan dengan kedudukan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, maka setiap lembaga negara dapatlah kemudian melakukan pengawasan dan mengimbangi lembaga negara yang lainnya. Adanya konsep saling mengawasi dan mengimbangi, tentunya telah memberikan suatu corak pemerintahan yang lebih baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ke depannya. Setidaknya, kejadian-kejadian seperti masa lalu dimana terjadinya penyalahgunaan kedaulatan rakyat oleh wakil rakyat sendiri dapat dibendung. Reformasi kelembagaan negara yang terjadi di Indonesia bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis (ICCE UIN,2010;76). Dalam konteks struktur ketatanegaraan Indonesia, maka lembaga negara adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam negara, sebagai wujud daripada kedaulatan rakyat yang kemudian dibalut dengan kedaulatan hukum. Cabang-cabang kekuasaan negara yang dimaksudkan dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan sistem pembagian maupun dengan konsep pemisahan kekuasaan yang menyertainya. Dan semuanya tentu disesuaikan dengan pandangan negara di mana konsep hubungan kelembagaan negara tersebut dianut.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
183
Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraaan yang kedudukannya independen yang berarti satu lembaga tentunya tidak akan dapat mengintervensi lembaga negara lainnya. Hal ini dikarenakan kedudukannya sejajar, yaitu secara horizontal bukan seperti dulu yang pembagian kekuasaannya antara lembaga negara ternyata menganut konsep secara vertikal. Akan tetapi, dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga negara yang satu tidak dapat terlepas ataupun terpisah secara mutlak dengan lembaga negara lain. Karena dalam menjalankan tugasnya setiap lembaga negara memerlukan suatu kerjasama, untuk dapat mencapai satu tujuan. Namun, demi tercapainya efisiensi maka pembagian kekuasaan merupakan suatu keniscayaan untuk mamu meningkatkan rasa tanggung jawab lembaga negara terhadap kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat. Hal itu juga menunjukan bahwa UUD 1945 tidaklah sepenuhnya menganut doktrin tentang pemisahan kekuasaan dalam arti materiil (separation of power), melainkan hanya menganut pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Senada dengan pernyataan di tersebut di atas, maka Maschab (1983;2) selanjutnya menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dianut sistem pembagian (fungsi) kekuasaan, dalam mana masing-masing bidang kekuasaan tersebut sama sekali tidak terpisah. Hal ini adalah konsekuensi logis dari sesuatu organisasi bahwa untuk berfungsinya suatu lembaga secara ideal, efisien dan efektif harus selalu diadakan interaksi dan koordinasi secara berimbang dan fungsional (Marbun,1994;6). Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Thalhah dan Malian (2011;37) bahwa adapun UUD 1945 menggunakan istilah-istilah yang berasal dari ajaran Trias Politika dari Montesquieu seperti legislative power, executive power, dan judicial power, hal itu tidak boleh diartikan bahwa UUD 1945 menganut ajaran tersebut. Penggunaan peristilahan itu hanyalah sekedar memberikan penjelasan dan perbandingan semata mengenai sistem ketatanegaraan yang sesungguhnya diikuti oleh UUD 1945. Dengan kata lain bahwa setiap lembaga negara perlu memiliki tugas yang jelas, tetapi sebagai suatu sistem ketatanegaraan, maka untuk mencapai tujuan sistem tersebut tentunya memerlukan suatu kerjasama yang apik antar lembaga negara yang ada, sehingga keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan tersebut merupakan suatu bagian yang tidak mungkin untuk dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal yang sama tentang sistem pembagian kekuasaan yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan juga dinyatakan kembali oleh pelaku sejarah yaitu, Yamin (dalam Marpaung,1999;7) yang menyatakan antara lain sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah mengenal ajaran trias politika yang membagi tugas dan pekerjaan pemerintahan atau perlengkapan negara menjadi tiga buah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
184
perlengkapan (organ) atau tiga buah jawatan (fungsi). Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas melaksanakan trias politika, yaitu membagi-bagi pekerjaan pemerintahan atau perlengkapan negara atas pelaksanaan dasar beberapa pembagian atau pemisahan (division atau separation of power) dengan tujuan untuk kelancaran pekerjaan dan untuk perlindungan warga negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. pembagian kekuasaan ini adalah sesuai dengan kebudayaan pribadi bangsa Indonesia Namun, tentunya pendapat tersebut di atas akan sangat berbeda dengan pendapat di bawah ini terkait dengan pembagian kekuasaan dalam UUD 1945. Tidak lain dikarenakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak dari Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002. Dalam kaitan dengan pernyataan tersebut, maka Indrati (2007;129) dalam hal ini berpendapat bahwa saat ini terdapat banyak pakar yang menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945, menganut ajaran Trias Politica, yang mengacu pada pemisahan kekuasaan (separation of power atau secheiding van machten), namun apabila dicermati ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam pasal-pasal UUD 1945 Perubahan, pendapat tersebut adalah tidak benar. Namun, dapatlah kemudian dilihat hasil dari perubahan-perubahan itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari 3 kali lipat jumlah materi muatan asli UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan (Asshiddiqie,2006;x). Selain itu, dengan adanya perubahan terhadap UUD 1945, telah pula mengembalikan kedudukan dan fungsi kelembagaan negara sesuai dengan dimaksud daripada dibentuk lembaga negara tersebut dalam UUD 1945. Hal ini menurut Asshiddiqie dalam Arifin dan Wardi (2002;5) bahwa dalam rangka perubahan UUD 1945, perkembangan gagasan untuk menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diwujudkan dalam pelembagaan organ-organ negara yang sederajat sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain (checks and balances). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap merupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca Perubahan Keempat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka untuk itu, terkait
I Gusti Ngurah Santika, SPd
185
pemisahan kekuasaan Asshiddiqie (2006;45) kemudian berpendapat bahwa UUD 1945 menganut paham pemisahan kekuasaan, tegasnya bahwa: paham yang dianut bukan pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal (horizontal separation of power), melainkan pembagian kekuasaan dalam arti vertikal (vertical distribution of power). Sekarang sejak diadakannya Perubahan Pertama yang kemudian dilengkapi lagi oleh Perubahan Kedua, Ketiga, Keempat UUD 1945, konstitusi negara kita meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan itu dan mengadopsi gagasan pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal (horizontal separation of power). Pemisahan kekuasaan itu dilakukan dengan menerapkan prinsip cheks and balances di antara lembaga-lembaga konstitusional yang sederajat itu yang diidealkan mengendalikan satu sama lain. Berkaitan dengan pemisahan kekuasaan yang sekarang dianut oleh UUD 1945, Sinaga (2008;17) mendukung pendapat di atas dengan menyatakan bahwa pandangan ini mendapatkan pijakan konstitusional dalam UUD 1945 hasil amandemen dimana kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di tangan presiden melainkan didistribusikan kepada berbagai lembaga negara. Begitu pun sebelumnya di mana ditentukan MPR yang merupakan lembaga negara tertinggi, bahkan sebagai pemegang kedaulatan rakyat, kemudian mendistribusikan (membagikan) kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara lainnya menurut UUD 1945. Sedangkan untuk sekarang, semua lembaga negara pada dasarnya memiliki kedudukan yang sederajat dengan tugas, fungsi dan wewenang yang sebelumnya diberikan oleh UUD 1945. Bahkan, dilengkapi pula dengan perubahan ketiga UUD 1945, dengan dibentuknya sebuah lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C UUD 1945). Dengan adanya MK, mencirikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem ketatanegaraan dengan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan mekanisme checks and balances, melalui pengujian undangundang terhadap UUD 1945 (toetsingrecht, yudicial review or constitutional review). Dengan adanya pembaharuan terhadap konstitusi yang kemudian disertai dengan dibentuknya lembaga negara baru, yang tentunya akan mempengaruhi hubungan antara lembaga-lembaga negara tersebut. Dengan demikian, maka berimplikasi pula terhadap hubungan di antara kelembagaan negara yang kemudian dianut oleh UUD 1945. Di mana dianutnya pemerintahan yang konstitusional dan kedaulatan rakyat (termasuk pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta pengecekan dan penyeimbangan ketiga kekuasaan tersebut) (Zuchdi,2009;40-41). Dengan demikian diharapkan tidak akan ada lagi dominasi oleh satu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lainnya. Berikut ini
I Gusti Ngurah Santika, SPd
186
merupakan penjelasan lembaga-lembaga negara setelah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali dalam suatu rangkain perubahan, yaitu sebagai berikut. C. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan UUD 1945 telah membawa pergeseran yang dapat dikatakan sangat mendasar, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ditandai dengan berkurangnya kekuasaan yang dimiliki oleh MPR, di mana pada awal mulanya dalam UUD 1945 adalah sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Ini merupakan salah satu hasil yang sangat positif daripada adanya amandemen terhadap UUD 1945, yang merubah kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, merupakan sebuah awal daripada memulai untuk diletakannya landasan guna terciptanya mekanisme checks and balances antara lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Berkaitan dengan hubungan antara kelembagaan negara, yang merupakan salah satu tujuan utama untuk diadakannya amandemen terhadap UUD 1945, adalah untuk menata kembali baik kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangannya yang tentunya akan berimplikasi pula terhadap keseimbangan (check and balance) antara lembaga negara. Hubungan itu ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara saja. apalagi, the central goal of a constitution is to create the precondition for wel-functioning democratic order. Dengan penumpukan kekuasaan pada satu institusi negara, kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratik tidak mungkin diwujudkan (Tutik,2008;90). Pada periode sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945 terkait dengan mekanisme checks and balances tidaklah mungkin dapat untuk dilakukan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Apalagi kemudian berkehendak untuk mengadakan suatu mekanisme checks and balances terhadap MPR, hal mana tidak mungkin dapat dilakukan. Karena sesuai dengan kedudukannya pada waktu itu dalam UUD 1945 sebelum diamandemen (amandement), MPR merupakan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kedudukan MPR sangat sentral dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut selanjutnya dapat diketahui sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
I Gusti Ngurah Santika, SPd
187
Permusyawaratan Rakyat (kursif penulis). Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus dinyatakan bahwa. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgen des Willens des staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Bahkan, jika kita kembali membaca dari Penjelasan khususnya ketentuan Pasal 3 UUD 1945 sebelum dihapus tersebut, terutama berkaitan dengan adanya kedaulatan rakyat yang dalam kenyataannya dipegang oleh MPR, bahwa di sana juga dinyatakan. Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, Menurut Manan dan Magnar (1997;111) bahwa penjelasan ini bertentangan dengan sendi-sendi pokok UUD 1945 sebagai negara yang berdasar atas hukum dan negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki pembatasan setiap kekuasaan. Dengan demikian, akan terlihat bahwa telah terjadi kontradiksi sendiri di dalam tubuh UUD 1945, terkait dengan apa yang diatur dalam sistem konstitusi dengan apa yang kemudian dikehendaki seperti apa tercantum di dalamnya tidaklah selaras. Karena apa yang seharusnya menjadi tujuan daripada konstitusi ternyata berbeda dengan apa yang kemudian diatur di dalamnya. Rumusan kedaulatan rakyat sebelum UUD 1945 diamandemen diletakan pada sebuah lembaga negara bernama MPR, lembaga inilah kemudian nantinya yang ditentukan, untuk bertugas guna melaksanakan kedaulatan rakyat yang harus sesuai dengan garis-garis petunjuk seperti apa yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Adanya konsekuensi dipusatkannya semua kekuasaan hanya pada satu lembaga negara tentunya akan membawa efeknya tersendiri, bahkan dapat dikatakan menjadi penyebab daripada tersumbatnya kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, tentunya akan menyebabkan terjadinya potensi penyalagunaan terhadap kedaulatan rakyat semakin besar. Selain itu, dengan meletakan suatu kedaulatan rakyat hanya kepada satu badan, akan menyebabkan pula ketidakseimbangan hubungan lembaga negara, karena kedudukan yang berbeda-beda antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain. Karena secara otomatis kedudukan lembaga-lembaga negara lain yang tidak memegang kedaulatan rakyat, yang telah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
188
ditentukan dalam UUD 1945 akan terlihat lebih rendah dari MPR, karena MPR telah ditentukan untuk memonopoli semua kedaulatan rakyat berada tangannya. Telah terbukti dalam sejarahnya, yang jika suatu kekuasaan ternyata terpusat, baik pada satu orang ataupun satu organ tentunya akan berpotensi untuk mengundang otoriterisme. Pernyataan di atas justru diakui sendiri oleh MPR RI, yang kemudian pada akhirnya berhasil merubah dengan meletakan kedaulatan rakyat pada tempatnya, bahkan kedaulatan rakyat harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip UUD 1945. Padahal rumusan sebelum perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, yang justru telah mereduksi paham kedaulatan rakyat menjadi paham kedaulatan negara, suatu paham yang hanya lazim dianut oleh negara yang masih menerapkan totalitarian dan/atau otoritarian (MPR RI,2011;61). Lebih lanjut terkait dengan adanya perubahan UUD 1945, terutama terhadap ketentuan mengenai kedudukan MPR yang sebelumnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah pemegang kedaulatan. Maka untuk MPR setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, ternyata tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat, karena MPR sendiri telah mengembalikan kedaulatan pada rakyat melalui amandemen 1945 sebagai sarananya, yaitu dengan tujuan utamanya adalah untuk meletakan kedaulatan rakyat agar nantinya dapat sesuai dengan posisinya seharusnya. Penyerahan kedaulatan rakyat melalui konstitusi merupakan satu-satunya jalur yang mungkin dapat ditempuh oleh MPR, dengan melakukan perubahan mendasar terhadap UUD 1945, khususnya berkaitan dengan pemegang kedaulatan rakyat. Sehingga untuk sekarang, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah diubah bunyinya menjadi Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, maka dalam kaitannya dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Mahmud MD (2009;35) kemudian menyatakan bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, secara teoritis berarti terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari sistem yang sebelumnya vertikal-hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara. Hal mana tentunya akan berbeda sekali dengan pengertian ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen, bahwa MPR dalam ketentuan tersebut dinyatakan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian dianggap pula sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan konsep yang demikian, sebenarnya UUD 1945 sebelum diamandemen telah menempatkan kedudukan MPR, sebagai lembaga negara yang paling tinggi diantara lembaga negara lainnya. Sehingga pengaturan tersebut telah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
189
berpotensi menjadikan kedaulatan rakyat yang dipegang oleh MPR, kemudian berubah menjadi kedaulatan negara, hal mana tentunya akan merugikan rakyat sendiri pemegang kedaulatan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Bahkan, konstruksi ini menunjukan bahwa MPR merupakan majelis yang mewakili kedudukan rakyat, sehingga menjadikan lembaga tersebut sebagai sentral kekuasaan, yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan yang lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi, membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara di bawahnya harus bertanggungjawab kepada MPR. Akibatnya, konsep keseimbangan antara elemen-elemen penyelenggara negara, atau bisa dipahami sebagai sistem checks and balances sistem antar lembaga tinggi negara, tidak dapat dijalankan. Karena itulah untuk membangun keseimbangan antara hubungan kelembagaan negara, maka dengan pemikiran yang cukup matang, dirasa perlulah kemudian untuk diadakan perubahan terhadap UUD 1945, terutama berkaitan dengan kedudukan MPR yang sebelumnya merupakan posisi kunci, bahkan penyebab utama tersumbatnya kedaulatan rakyat, karena hanya dimonopoli oleh satu lembaga, seperti apa yang disebutkan dalam UUD 1945. Sistem ketatanegaraan yang dianut sebelumnya oleh UUD 1945 adalah vertical hierarkis, yang menempatkan MPR sebagai satu-satunya lembaga negara yang paling tinggi di antara yang lainnya. Sebelum perubahan kedudukan MPR dalam UUD 1945 adalah sebagai pemegang kuasa atas kedaulatan rakyat, untuk selanjutnya kedaulatan rakyat tersebut didistribusikannya kepada lembaga-lembaga negara lainnya, sehingga dalam hal ini kemudian dikenal dengan istilah pembagian kekuasaan (distribution of power). Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Jimly Asshiddiqie (2009;190) yang menyatakan bahwa dengan perubahan ini berarti UUD 1945 tidak lagi menganut sistem MPR berdasarkan prinsip supremasi parlemen dan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) oleh lembaga tertinggi MPR ke lembaga-lembaga negara di bawahnya. Dan sekarang dengan adanya perubahan susunan dan kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka sistem yang dianut adalah sistem pemisahan kekuasaan dengan mekanisme check and balances diantara lembaga-lembaga negara. Pasalnya, berdasarkan UUD 1945 yang diamandemen tentang eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang MPR, ia bukan lagi lembaga wakil rakyat yang tinggi dan tertinggi. Dan bukan juga sebagai lembaga yang sangat berkuasa, seperti sebelumnya (Isra,2010;31). Dengan demikian, kedudukan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya adalah sama, sehingga dapat pula untuk saling mengawasi dan mengimbangi (checks and
I Gusti Ngurah Santika, SPd
190
balances), sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan yang kemudian diberikan oleh UUD 1945 setelah perubahan. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, selain telah mengubah kedudukan daripada MPR sebagaimana dimaksudkan penjelasan tersebut di atas. Maka disusul pula dengan terjadi perubahan terhadap susunan keanggotaan MPR, yang dalam kenyataannya berubah secara struktural, terutama karena dihapuskannya keberadaan daripada Utusan Golongan, yang sebelum UUD 1945 diamandemen mencerminkan prinsip dari perwakilan fungsional (fungsional representation), yang merupakan salah unsur keanggotaan dari MPR. Sebelum amandemen UUD 1945 berkaitan dengan susunan keanggotaan MPR telah dinyatakan dengan tegas pula, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang(kursif penulis). Dengan demikian, dalam sejarah perjalanannya, bahwa MPR yang notabene, ditentukan merupakan pemegang kuasa atas kedaulatan rakyat, bahkan ditentukan sepenuhnya sebagai pelaksana daripada kedaulatan rakyat, yang secara tegas tercantum dalam ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen. Namun, dapatlah dilihat kembali ketentuan tersebut, yang dalam kenyataannya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen, menyerahkan pengaturannya lebih lanjut hanya dengan sebuah undang-undang, yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Tentu apa saja yang kemudian diatur di dalamnya berkaitan dengan MPR, baik mengenai kedaulatan, kedudukan, keanggotaanya, tugas, fungsi dan wewenangnya, maupun berkenaan hal lainnya. Bahkan pendek kata sebenarnya undangundanglah yang nantinya paling menentukan nasib daripada pemegang kedaulatan ini. Padahal jika cermati kembali secara saksama terhadap ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang sebenarnya merupakan produk hukum yang kemudian dibuat oleh lembaga negara lain, seperti ditentukan dalam UUD 1945. Yang tentu saja, pada waktu itu kedudukan kedua lembaga negara tersebut (DPR dan Presiden) yang fungsinya sebagai pembentuk undang-undang ternyata berada di bawah MPR menurut UUD 1945 sebelum amandemen. Dengan demikian, kemungkinan besar ke depannya jika saja terjadi kolaborasi yang sifatnya negatif, antara DPR dan Presiden sebagai lembaga negara yang berwenang dalam membentuk undang-undang, tentunya akan membawa dampak tersendiri terhadap MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Padahal dapat diketahui bahwa kedudukan kedua lembaga tersebut sebenarnya berada persis di bawah MPR. Namun konstitusi telah memberikan kewenangan untuk selanjutnya menafsirkan ketentuan konstitusi, terkait
I Gusti Ngurah Santika, SPd
191
dengan seberapa besar kedaulatan rakyat yang selanjutnya akan dipegang oleh MPR. Karena memang DPR dan Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menafsirkannya adalah berdasarkan atribusi yang telah ditentukan sendiri dalam UUD 1945, untuk kemudian mengaturnya lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, kewenangan Presiden dan DPR dalam hal pembentukan undang-undang, tentunya mempunyai kekuasaan penuh untuk kemudian mengatur berkenaan dengan seluk beluk MPR. Dengan demikian, dapat dikatakan telah menyebabkan MPR menjadi lembaga negara, yang boleh untuk dinyatakan sebenarnya tidak lagi memegang kedaulatan rakyat serta tidaklah pula memiliki kedudukan yang tertinggi menurut UUD 1945. Kedaulatan rakyat yang sebenarnya dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah menurut undang-undang, yang sebelumnya ditetapkan oleh dua lembaga yang berwenang, yaitu DPR dan Presiden menurut UUD 1945. Dengan demikian, MPR bukanlah sebagai pemegang kedaulatan rakyat dalam arti sesungguhnya, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Bahkan, MPR ditentukan kedudukannya sebagai lembaga negara tertinggi, ternyata dalam pengaturan mengenai pengisian keanggotaannya diberikan kepada lembaga negara lainnya, yang mana notabene berkedudukan di bawahnya. Pengaturan sebagaimana dimaksudkan, adalah baik mengenai jumlah, maupun tatacara pemilihan anggota MPR, yang tentunya juga dalam hal ini adalah termasuk hak dan kewajiban anggotanya. Oleh karenanya, dapatlah kemudian dikatakan bahwa sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945 berkaitan dengan pengaturan MPR, baik berupa pengisian keanggotaan maupun lain-lainnya, telah ditentukan secara tegas, untuk diatur kembali oleh dua lembaga negara tersebut (DPR dan Presiden). Kedua lembaga negara tersebut merupakan lembaga yang sama-sama memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, yang bahkan dapat dipastikan bahwa kedudukan kedua lembaga negara ini, sebenarnya berada di bawah MPR. Dalam hal ini, sebenarnya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh MPR, akan lebih banyak ditentukan oleh undang-undang, bukannya oleh konstitusi. Dengan demikian, pemegang kedaulatan rakyat (MPR) akan sangat bergantung pada kehendak dari DPR dan Presiden, yang menurut konstitusi harus mengatur lebih lanjut ketentuan berkaitan dengan MPR dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan kehendak kedua lembaga tersebutlah, akan terbentuk sebuah undang-undang dengan tujuan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kelembagaan MPR. Hanya saja, suatu kehendak pembentuk undangundang, kadang-kadang bahkan bisa saja tidaklah selalu selaras dengan apa yang kemudian dikehendaki oleh konstitusi itu sendiri. Sehingga, bisa jadi kehendak norma hukum konstitusi yang sebelumnya ditafsirkan oleh DPR dan Presiden adalah sesuai dengan jiwa konstitusi, maka MPR tentunya akan tetap memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
192
sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Hal mana tentunya adalah sesuai dengan kehendak rakyat, yang sebenarnya memberikan kedaulatannya melalui konstitusi kepada MPR, dengan kembali mengatribusikan pengaturannya lewat undang-undang. Ataukah sebaliknya suatu saat DPR dan Presiden yang kemudian memberikan tafsiran terhadap MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, dalam kenyataannya berbeda dengan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh UUD 1945. Melainkan tafsiran tersebut hanya menyesuaikan dengan kehendak pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi, semua pengaturannya terutama tentang kedaulatan MPR, akan sangatlah tergantung kemudian, pada kehendak para pembentuk undang-undang itu sendiri. Hanya saja yang terlihat selama ini berkaitan dengan kehendak daripada UUD 1945 dalam pengaturannya kembali dengan bentuk undang-undang, terutama tentang pemegang kedaulatan rakyat, ternyata apa yang kemudian diatur oleh DPR dan Presiden, adalah jelasjelas tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dikehendaki konstitusi. Dengan demikian, tentunya telah terjadi pertentangan antara prosedur yang dianut, dengan prinsip-prinsip negara yang bentuk pemerintahannya demokratis, terutama dalam kaitannya dengan pengaturan pemegang kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kesimpulan yang kemudian diperoleh untuk sementara waktu, adalah MPR itu sendiri pada periode sebelum amandemen UUD 1945, sebenarnya tidaklah memegang kedaulatan rakyat secara utuh, seperti apa yang digembar gemborkan oleh UUD 1945. Terbukti jelas sekali dalam sejarah perjalanannya, terkait dengan penafsiran-penafsiran yang kemudian diberikan oleh pembentuk undang-undang, terhadap pengisian keanggotaan dalam tubuh MPR. Hal tersebut jelas tdapat diketahui, kerena sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, seperti adanya kata golongan-golongan, ternyata oleh pembentuk undang-undang kemudian ditafsirkan kembali dengan memasukan angkatan bersenjata sebagai salah satunya, yang untuk itu dinyatakan memiliki hak untuk duduk dalam pengisisan keanggotaan di MPR. Pada awal mula ditetapkannya pengisian keanggotaan di MPR, yang di dalamnya terdiri dari DPR, Utusan-Utusan Daerah dan golongan-golongan yang menurut Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus dinyatakan, bahwa yang kemudian dimaksudkan dengan utusan golongan yaitu: Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
193
Yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi. Maksud utama daripada Penjelasan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum dihapus, adalah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan memiliki wakilnya dalam Majelis, sehingga Majelis itu tentunya akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Bahkan dalam penjelasan pun, sudah dijelaskan dengan tegas, yang selanjutnya disebut dengan golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif. Lebih lanjut, maksudnya adalah untuk memasukan unsur golongan-golongan seperti tersebut di atas adalah memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubungan dengan itu anjuran untuk mengadakan sistem ekonomi, maka ayat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi. Dari Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, dapatlah diketahui dengan jelas, apa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah badan-badan ekonomilah yang kemudian disebut dengan golongan-golongan, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum dihapus, bukannya militer. Dalam rangka itu perlu diakui bahwa ada masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan yaitu bagaimana menetapkan patokan obyektif mengenai sifat-sifat golongan fungsional yang akan diikutsertakan, dan bagaimana menentukan kriteria untuk mengukur kekuatan golongan fungsional masingmasing (Budiardjo,2008;319). Dengan demikian, setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, terkait dengan pengisian keanggotaan MPR, yang kemudian hanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 setelah diamandemen. Bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 setelah diamandemen, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang (kursif penulis). Berkaitan dengan struktur MPR hal mana ditentukan terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, yang kemudian tata cara pengisian keanggotaannya telah ditentukan, yaitu melalui pemilihan umum, ternyata dapat juga dijumpai dalam pengaturannya lebih lanjut terkait dengan MPR, yaitu UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
194
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tepatnya dalam ketentuan Pasal 2 undang-undang tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat mencerminkan prinsip perwakilan politik (political representation) yang mewakili rakyat secara keseluruhan, yaitu rakyat Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan pencerminan dari prinsip perwakilan daerah (regional representation), yang dalam hal ini merupakan perwakilan dari masing-masing daerah provinsi di seluruh Indonesia. Perubahan ketentuan mengenai susunan keanggotaan MPR, tiada lain dimaksudkan untuk semakin mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang seluruh anggota MPR ditentukan untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu, perubahan itu untuk meningkatkan legitimasi MPR. Dengan perubahan ketentuan tersebut, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang semuanya dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Ketentuan itu sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu perwakilan atas dasar pemilihan (representation by election). Sehingga rakyat betul-betul memegang kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya, berupa kekuasaan untuk menentukan siapa wakil-wakilnya yang nantinya duduk di MPR. Dengan demikian, terlihat bahwa rakyat memiliki kedaulatan terhadap penentuan siapa saja yang dapat menjadi anggota MPR. Kalau kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara, maka kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat (Soemantri,1992;20). Kedaulatan sebagai ekspresi yuridis dari kekuasaan tertinggi menjadi kerangka tempat ide demokrasi dapat ditemukan dalam kekuasaan tertinggi di tangan rakyat (teori kedaulatan rakyat) (Nurtjahjo,2006;29). Intinya bahwa berkaitan dengan kedaulatan rakyat terutama dalam pemilihan anggota yang duduk dalam badan perwakilan, tercermin dengan tidak adanya lagi anggota MPR yang diangkat oleh Presiden seperti masa lalu. Di mana ketika itu sebagian besar keanggotaannya diangkat oleh Presiden Soeharto, sehingga lembaga ini nyaris tidak dapat berfungsi, terutama dalam melakukan checks and balances kekuasaan Presiden. Karena dapat dipastikan bahwa anggota-anggota yang kemudian dipilihnya tentu akan selalu loyal hanya terhadap orang yang telah mengangkatnya. Walaupun sebenarnya dalam perjalanannya banyak yang kemudian menentang adanya sistem pengangkatan anggota MPR oleh Presiden. Dikarenakan terlalu banyaknya anggota-anggota MPR yang kemudian diangkat, sehingga dapatlah kemudian dikatakan bahwa sebelum Perubahan UUD 1945, MPR dikatakan sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang sekaligus ditentukan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tidaklah dapat dikatakan sepenuh benar. Sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, dengan adanya sistem pengangkatan anggota MPR terutama dari
I Gusti Ngurah Santika, SPd
195
unsur Utusan Daerah dan Utusan Golongan, bagi pembentukan MPR dalam jumlah yang demikian besar juga dapat dilihat sebagai suatu penyimpangan konstitusional yang dilakukan oleh Orde Baru. Karena secara logika dan dalam kenyataan juga akan terlihat bahwa wakil yang diangkat akan patuh dan loyal pada pihak yang mengangkatnya, sehingga wakil tersebut tidak lagi mengemban kepentingan daerah atau golongan yang diwakilinya. Dengan demikian, akan mengaburkan konsep perwakilan yang dianut dalam sistem perwakilan Indonesia. Akibatnya adalah wakil-wakil yang diangkat itu tidak lagi memiliki hubungan dengan yang diwakilinya, hubungan terjadi hanya pada orang yang mengangkatnya, sedangkan rakyat tidak memiliki kekuasaan terhadap wakil tersebut karena rakyat tidak memilihnya. Yang menjadi latar belakang adanya sistem pengangkatan terhadap anggota yang duduk di MPR, merupakan suatu konsensus yang tercapainya pada 27 Juli 1967 antara pihak pemerintah dan partai-partai politik, terkait dengan model sistem pemilihan umum yang akan digunakan. Dimana pada saat itu diusulkan oleh pihak pemerintah untuk sistem pemilihan umum yang digunakan adalah dengan sistem distrik. Namun, patut disayangkan ternyata banyak mendapat penolakan dan sempat menimbulkan perdebatan panjang, yang akhirnya kemudian disepakati untuk menggunakan model pemilihan umum dengan sistem proporsional, yang mana terutama sangat diinginkan oleh partai-partai politik ketika itu. Namun, dilain pihak partai-partai politik pada waktu itu mengalah, yaitu dengan menerima syarat dari pemerintah, bahwa 100 anggota parlemen yang dari jumlah total pada saat itu 460 akan diangkat oleh Presiden, terutama dari golongan ABRI (75) dan non ABRI (25) dengan adanya jaminan sebagai ketentuan bahwa golongan militer tidak akan menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih. Perlu diketahui berkaitan lebih lanjut terkait dengan susunan keanggotaan MPR itu sendiri pada saat dalam proses amandemen UUD 1945 oleh MPR, merupakan suatu materi perubahan yang bisa kemudian digolongkan sangatlah sulit untuk mendapatkan kesepakatan di antara anggota-anggota MPR yang ketika itu melakukan perubahan. Dengan demikian, dari berbagai materi yang telah dirubah dan disepakati sebelumnya oleh MPR, ternyata ada satu ketentuan yang merupakan hasil dari amandemen terhadap UUD 1945, namun ternyata dalam mengambil keputusannya dilakukan dengan suara terbanyak (voting). Kemudian dari berbagai perdebatan yang berlangsung begitu panjang dan juga melelahkan, pada akhirnya hanya terdapat dua alternatif tentang susunan keanggotaan MPR. Yang merupakan alternatif pertama yaitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan golongan yang dipilih oleh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
196
Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang. Sedangkan untuk alternatif yang kedua yaitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Menurut keterangan yang kemudian didapat dalam buku Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (2011;48) yang mana dinyatakan bahwa pada pemungutan suara tersebut, mayoritas anggota MPR memilih alternatif 2, yaitu sebanyak 475 anggota MPR, sedangkan alternatif 1 dipilih 122 anggota MPR, dan 3 anggota MPR memilih abstain. Berkaitan dengan adanya perubahan terhadap susunanan keanggotaan MPR, yang hanya terdiri dari anggota DPR dan DPD sebagai hasil daripada pemilihan umum. Maka untuk nantinya diharapkan bahwa seluruh anggotanya merupakan pilihan rakyat, karena memang telah ditentukan dipilih secara langsung agar benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat sendiri. Selain sebagai mana dimaksudkan dalam penjelasan tersebut di atas, maka dalam ketentuan itu juga telah menyiratkan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, yang secara otomatis telah mengubah lembaga perwakilan dari model satu setengah kamar kemudian menjadi model dua kamar. Pada awal mula perubahan terhadap kelembagaan MPR, memang pada waktu itu muncul ide untuk membentuk model perwakilan dua kamar, yang nantinya akan terdiri dari DPR dan DPD, untuk membentuk sidang gabungan yang kemudian diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Winardi (2008;47) ada 3 alasan untuk mengubah MPR menjadi lembaga perwakilan dua kamar, yaitu. 1. Kebutuhan dalam pembenahan sistem, sehubungan dengan berbagai permasalahan dalam sistem MPR yang lama. Anggota MPR yang bukan anggota DPR yaitu Utusan Daerah dan Utusan Golongan tidak berfungsi efektif dan tidak jelas orientasi keterwakilannya; 2. Kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat daerah secara struktural. Dengan adanya DPD masyarakat di daerah akan dapat diakomodasikan melalui institusi formal di tingkat nasional; 3. Kebutuhan bagi Indonesia saat ini mulai menerapkan sistem checks and balances dalam rangka memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan mendorong demokratisasi.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
197
Memang pada awal-awal dilaksanakannya amandemen terhadap UUD 1945, terdapat wacana bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dirancang, untuk diubah menjadi genus dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen Indonesia yang terdiri atas dua kamar. Kamar pertama merupakan Dewan Perwakilan Rakyat dan kamar kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah. Prinsip yang sama dapat kita temukan pada konstitusi Amerika Serikat yang menentukan bahwa semua kekuasaan legislatif ada di Konggres yang terdiri atas the House of Representatives and senate. Demikian pula dengan Kerajaan Belanda yang di dalam konstitusi tersebut menyatakan bahwa kekuasaan legislatif berada di Staten Generaal yang terdiri atas Erste Kameren een Tweede Kamer (Asshiddiqie,2003). Kemudian lebih lanjut, menurut Harjanti (2009;12) yang menyatakan pendapatnya tentang pertimbangan untuk diadakannya sistem parlemen dua kamar, yaitu. Beberapa pertimbangan penerapan sistem dua kamar adalah sebagai berikut: terciptanya mekanisme checks and balances antara kamar-kamar dalam satu badan perwakilan, penyederhanaan sistem badan perwakilan karena penghapusan utusan golongan, wakil daerah menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi parlemen sehingga kepentingan daerah dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan parlemen, menciptakan produktivitas karena tugas dan wewenang dapat dilakukan setiap unsur. Dengan demikian dari aspek akademis terlihat bahwa reformasi sistem perwakilan ditujukan ke arah bicameral system. Memang dengan menggunakan parlemen yang sistemnya bikameral tentunya akan memiliki keunggulan tersendiri, seperti argumen yang kemudian digunakan oleh C.F Strong (2005;273) untuk mendukung parlemen dengan sistem dua kamar tersebut, yaitu pertama, keberadaan kamar kedua dapat mencegah pengesahan undang-undang secara tergesa-gesa dan tidak direncanakan secara matang oleh satu majelis. Kedua, khusus negara federal, dibuat sedemikian rupa untuk mendukung prinsip federal atau melindungi kehendak rakyat dari setiap negara bagian, yang berbeda dengan kehendak federasi sebagai suatu keseluruhan. Seperti apa yang dikemukakan Strong di atas, khususnya terkait dengan pendapat kedua tentu hanyalah berkaitan dengan keuntungan, yang akan diperoleh oleh negara-negara federal terkait dengan parlemen yang menganut model dua kamar, di mana nantinya bertujuan untuk menjaga kelangsungan daripada bentuk negara, yaitu serika. Namun, untuk itu, dapatlah kemudian dinyatakan dengan pendapat yang juga tidak jauh berbeda, seperti tersebut di atas, maka oleh Prodjodikoro (1981;72) terkait dengan keuntungan dari sistem parlemen dua kamar, yang dianut oleh suatu negara, maka dapatlah dikatakan bahwa alasan untuk mengadakan sistem dua badan legislatif, yang dapat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
198
diketemukan oleh para penulis, sebenarnya hanya satu, yaitu untuk menjaga, jangan sampai tergesa-gesa ada undang-undang baru atau perubahan undang-undang lama, maka rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR (House of Representatives, pen), dibahas lagi oleh Senat, agar undang-undang baru atau perubahan undang-undang betulbetul matang untuk diperlakukan oleh segenap warga negara dan penduduk. Selain itu, menurut Winardi (2008;55) berpendapat bahwa keuntungan yang mungkin diperoleh dari adanya sistem legislatif dengan model bikameral, yaitu. 1. Secara resmi mewakili beragam pemilih (misalnya negara bagian, wilayah, etnik, atau golongan); 2. Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan perundang-undangan; 3. Mencegah disahkannya peraturan perundang-undangan yang cacat atau ceroboh; 4. Melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif. Namun, apa yang seperti dikemukakan oleh Strong dkk seperti tersebut di atas, hanyalah merupakan kebaikannya saja terutama jika suatu negara menganut sistem parlemen dengan model dua kamar. Akan tetapi dalam prakteknya, adanya dua badan seringkali menimbulkan deadlock, dan pergeseran antara yang satu dengan badan yang lainnya, dan menimbulkan banyak pembiayaan (Lubis,1980;80). Sehingga bisa saja, dalam pembahasan terutama ketika saat proses pembentukan undang-undang akan memerlukan waktu yang cukup lama, tidak lain dikarenakan adanya perdebatan yang berkepanjangan, di antara dua kamar dalam badan tersebut. Sedangkan disatu pihak, dalam menanggapi situasi seperti sekarang ini, yang dengan demikian cepatnya berubah, dikarenakan perkembangan dinamis kehidupan suatu bangsa. Maka sebagai negara hukum tentunya akan melakukan tindakan memerlukan dasar hukum yang juga cepat, terutama dalam bentuk undangundang, namun bisa saja yang terjadi kemudian menjadi sangat lambat dalam pembuatannya. Mungkin saja diakibatkan oleh adanya perbedaan persepsi antara kedua kamar dalam badan tersebut, terkait dengan materi dari rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Namun, pada akhirnya hanya akan mengabiskan energi dan biaya serta ditambah dapat menghambat tugas-tugas pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Padahal hal tersebut merupakan tujuan awal mula dibentuknya parlemen dengan model dua kamar.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
199
Kemudian berkaitan dengan tugas dan wewenang MPR yang ditentukan dalam UUD 1945 adalah tersebar, baik selanjutnya yang telah diatur dalam Bab tentang MPR, maupun kemudian dalam Bab Pemerintahan Negara dan lain-lainnya, seperti apa yang dinyatakan dalam UUD 1945. Namun, kemudian ditentukan dalam UU No. 27 Tahun 2009, tepatnya dalam ketentuan Pasal 4 yang pada dasarnya telah mengatur semua tugas dan kewenangan MPR, di mana dalam UUD 1945 ditentukan tersebar, kemudian di dalam undang-undang tersebut dijadikan satu. Tugas dan kewenangan MPR sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut. 1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; 3. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya; 4. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan; 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Tugas dan kewenangan MPR sebagaimana dimaksudkan seperti tersebut di atas, tentunya akan diusahakan untuk dibahas di bawah ini secara satu persatu. Di mana pembahasan tersebut, akan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan terutama dengan ketentuan sebelum perubahan terhadap UUD 1945, dengan tujuan agar mendapatkan sedikit tambahan penjelasan. MPR yang merupakan suatu lembaga negara, kemudian telah ditentukan dengan tegas memiliki suatu kewenangan untuk merubah dan menetapkan UUD 1945, seperti apa yang kemudian diamanatkan sendiri oleh Undang-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
200
Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar. Sebelum dilakukan amandemen terhadap ketentuan Pasal 3 UUD 1945, ternyata dalam ketentuan Pasal 3 UUD 1945 terdahulu, tidaklah terdapat ayat tambahan, hal mana tidak lain dikarenakan pada waktu itu, hanya terdapat satu pasal saja dengan tidak terdapat ayat tambahan, yang mana tentunya akan berbeda sekali dengan ketentuan sekarang, yang di dalam pasal tersebut terdiri dari tiga ayat tambahan sebagai hasil dari amandemen. Bunyi dari ketentuan Pasal 3 UUD 1945 sebelum diamandemen yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Dalam pasal tersebut terdapat kata menetapkan, apakah menetapkan sama dengan kata mengubah? Menurut pendapat penulis yang pertama, bahwa kata menetapkan dalam pasal tersebut berarti bahwa MPR hanya berwenang untuk menetapkan UUD 1945, yang dahulunya ketika disahkan oleh PPKI, dikuatkan kemudian dengan pendapat Soekarno, bahwa UUD 1945 tersebut adalah masih bersifat sementara. Bilamana pengertian demikian yang kemudian diberikan, maka secara otomatis, bahwa MPR tentunya tidaklah memiliki kewenangan sama sekali untuk melakukan suatu perubahan terhadap UUD 1945. Namun, MPR hanya berwenang untuk mengukuhkan, apa yang sebelumnya telah ada dalam UUD 1945, sehingga UUD 1945 tersebut kemudian menjadi bersifat tetap, yang semula menurut sejarah hanyalah bersifat untuk sementara waktu. Namun, tentunya kita tidak hanya berpedoman pada bunyi ketentuan dari Pasal 3 UUD 1945 sebelum diamandemen. Dikarenakan berkaitan dengan kewenangan MPR untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, ternyata juga diatur kembali dalam ketentuan Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan, yang mana di dalamnya menyatakan bahwa MPR lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, dengan berbagai syarat yang menyertainya kemudian. Dalam Bab XVI Pasal 37 UUD 1945 sebelum diamandemen dinyatakan bahwa. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir (kursif penulis). 2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir (kursif penulis). Setelah amandemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR, dalam kenyataannya terkait dengan kedudukan MPR, untuk kemudian melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 menjadi semakin kuat. Dengan demikian, tidak ada lembaga negara lainnya yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, selain MPR. 1.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
201
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 telah memperjelas dan mempertegas kedudukan MPR, dalam kewenangannya melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945. Adanya ketentuan ini merupakan sebuah jawaban tegas terhadap perdebatan pada waktu reformasi, di mana ketika itu telah terjadi suatu perdebatan mengenai kewenangan MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Perdebatan tersebut berkisar antara kewenangan MPR untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 (dalam arti hanya MPR saja yang memiliki hak untuk melakukan perubahan) dan diberikannya hak kepada masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, misalnya dengan membentuk suatu Komisi Konstitusi. Nantinya, diharapkan dengan dibentuknya suatu Komisi Konstitusi yang sifanya independen terutama dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, untuk selanjutnya hasil yang merupakan buah kerja dari komisi tersebut diajukan kepada MPR untuk kemudian diterima (dikukuhkan) ataukah ditolak. Jika nantinya ternyata hasil kerja dari Komisi Konstitusi tersebut diterima, maka MPR berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 sebelum diamandemen, dapatlah kemudian menetapkannya sebagai UUD yang baru. Maka, untuk sekarang ini terutama setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945, khususnya berkenaan dengan ketentuan dari Pasal 3 ayat (1)UUD 1945. Maka dapatlah kemudian disimpulkan bahwa, hanya MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan secara legal konstitusional untuk selanjutnya melakukan perubahan terhadap padal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Namun tentunya dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, telah ditentukan prosedur yang nantinya perlu ditempuh untuk dapat dinyatakan, bahwa perubahan yang dilakukan MPR terhadap UUD 1945 adalah sah, sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, khususnya dalam ketentuan Pasal 37. Kemudian dalam ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang isinya terdiri dari 5 ayat merupakan tata cara MPR dalam melakukan perubahan terhadap pasal Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengetahui secara lebih lengkap ketentuan Pasal 37 UUD 1945, maka dapatlah dikutipkan isinya tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
202
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan (kursif penulis). Terlihat dengan jelas bahwa dari ayat-ayat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 37 UUD 1945 tersebut, telah menentukan bahwa dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, ternyata tidaklah mungkin dapat dilakukan secara menyeluruh (komperhensif), di mana UUD 1945 untuk sekarang terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal, yang kemudian dipertegas kembali dalam Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945. Hal ini tentunya akan berbeda sekali dengan sebelum diamandemennya UUD 1945, yang di dalam ketentuan Pasal 37 UUD 1945 dapat diberikan tafsiran, bahwa MPR pada waktu itu dapat saja melakukan suatu penggantian terhadap UUD 1945, yaitu menggantinya dengan UUD yang sama sekali baru. Ketentuan Pasal 37 UUD 1945 sebelum amandemen, dalam ayat (1) tersebut menyatakan bahwa Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurangkurangnya 2/3 daripada jumlah Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir (kursif penulis). Dalam bunyi pasal tersebut sangatlah jelas dinyatakan bahwa MPR dapat mengubah UUD 1945 (tanpa menyebut pasal-pasal/Batang Tubuh UUD 1945). Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa kewenangan MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, di dalamnya termasuk perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 yang cukup dilakukan hanya dengan dukungan 2/3 jumlah keseluruhan anggota MPR yang harus hadir. Namun, terkait dengan keputusan untuk dinyatakan sahnya suatu perubahan terhadap UUD 1945 oleh MPR, dinyatakan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen yang berbunyi bahwa Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. Dengan demikian, adanya amandemen terhadap UUD 1945, khususnya terhadap ketentuan dalam Pasal 37 tentang Perubahan UUD 1945 ternyata kemudian membawa implikasi. Terutama persyaratannya yang kemudian menjadi semakin sulit, untuk nantinya ketika berkeinginan melakukan perubahan terhadap UUD 1945, apalagi ada kehendak untuk melakukan suatu perubahan UUD 1945 secara komperhensif. Hal mana dikarenakan, dalam ketentuan ayat (1) dari Pasal 37 UUD 1945 setelah diamandemen, dinyatakan di dalamnya bahwa, jika ada suatu usul perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945, untuk dapat diagendakan saja dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
203
sidang MPR, setidaknya-tidaknya haruslah mendapat dukungan suara 1/3 dari anggota MPR. Dengan kata lain, jika dukungan suara di MPR tentang usul perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 ternyata tidak mendapat dukungan suara 1/3 dari anggota MPR, maka rencana yang berbentuk usul perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945, tidaklah mungkin dapat kemudian untuk diagendakan dalam sidang MPR. Selain adanya ketentuan tersebut, maka dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, haruslah terlebih dahulu diajukan usul terhadap salah satu pasal yang ingin diadakan perubahan dengan menunjuk jelas, bahkan terkait dengan usul tersebut haruslah disertai pula alasan yang cukup kuat mengapa pasal dalam UUD 1945 tersebut perlu dirubah. Untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, sudah ditentukan sebelumnya dengan jelas haruslah mendapat dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian barulah putusan untuk melakukan perubahan terhadap Pasal-pasal UUD 1945 harus mendapat persetujuan 50% +1 dari seluruh anggota MPR. Dengan demikian, terlihat bahwa persyaratan dalam melakukan perubahan sangat sulit, apalagi ingin melakukan perubahan secara komperhensif. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Mahmud MD (2009;195) bahwa dengan ketentuan yang demikian akan sangat sulitlah melakukan perubahan untuk satu paket (keseluruhan isi) UUD karena arahnya mendorong perubahan pasal-perpasal saja sehingga agak sulit untuk melakukan perubahan secara komperhensif dengan konstruksi yang baru. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan dasar pada saat akan dilakukan perubahan tahun 1999 bahwa perubahan hanya akan dilakukan dengan addendum. Lebih lanjut terkait dengan pengaturan perubahan terhadap UUD 1945, ternyata ada satu ketentuan berupa ayat (5) dari Pasal 37 UUD 1945, yang pada dasarnya telah membatasi kewenangan MPR, untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Khusus mengenai Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dengan demikian, menurut penulis dalam hal ini, setidaknya ditentukan ada dua hal yang kemudian tidak mungkin dapat untuk dilakukan oleh MPR, terkait kewenangannya dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945. pertama, ketentuan yang menyatakan secara implisit bahwa Pembukaan UUD 1945 tidaklah mungkin dapat dilakukan perubahan. Karena cukup jelas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 bahwa MPR hanya berwenang melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa secara tidak langsung MPR telah memisahkan kedudukan hukum antara Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasalnya. Dengan demikian, secara tidak langsung dapatlah kemudian dikatakan bahwa kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
204
daripada pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945. Pendapat tersebut dinyatakan, dikarenakan bahwa di dalam Pembukaan UUD 1945 sendiri terdapat Pancasila yang memang merupakan suatu norma dasar (basic norma), yang dapat dikatakan fundamental kedudukannya dalam negara (staatfundamentalnorm). Bahkan, di dalam suatu negara, norma dasar ini disebut juga dengan nama Staatsfundamentalnorm. Staatsfundamentalnorm suatu negara merupakan dasar filosofisnya yang di dalamnya mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut (Indrati,2007;46). Bahkan, Hans Nawiasky menyatakan bahwa isi daripada Staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (Staatverfassung), termasuk norma pengubahnya. Terkait dengan norma dasar, maka Joeniarto (1996;7) berpendapat bahwa Pancasila dilihat dari segi lain, oleh karena merupakan norma yang pertama yang merupakan sumber berlakunya daripada segala macam norma/aturan/ketentuan hukum yang lainnya. Dengan demikian, kedudukan daripada Pancasila itu sendiri sebenarnya berada di luar UUD 1945. Oleh karena Pembukaan itu sesungguhnya berada di luar Undang-Undang Dasar 1945, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak berwenang mengubah atau mengganti bagian atau bagianbagian tertentu dari Pembukaan (Soemantri,1992;67). Sedangkan terkait dengan larangan lainnya bagi MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yang merupakan pendapat kedua penulis adalah tidak dapat dilakukannya perubahan oleh MPR yang dalam ayat (5) dari ketentuan Pasal 37 UUD 1945, terkait masalah mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian pengaturan larangan tersebut terlihat secara eksplisit. Bahkan, ketentuan ini kemudian dipertegas kembali di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009, yang pada dasarnya menyatakan bahwa. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (kursif penulis). Selain kewenangan MPR untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945, ternyata dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945, MPR juga memiliki kewenangan lainnya, yaitu untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden, selengkapnya berbunyi bahwa Majelis Permusyawaratan melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (kursif penulis). Pasal ini tentunya memiliki kaitan dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
205
yang kemudian di dalam ketentuan Pasal 8 UUD 1945 itu, terdiri dari 3 ayat yang bunyinya secara lengkap, yaitu sebagai berikut. 1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. 3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya (kursif penulis). Dengan demikian, bilamana menurut ketentuan dalam Pasal 8 UUD 1945 tersebut telah terpenuhi, maka MPR kemudian akan mengangkat Wakil Presiden untuk selanjutnya menjadi Presiden. Dikarenakan dengan alasan bahwa Presiden sebelumnya telah mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Dengan diangkatnya, Wakil Presiden terdahulu untuk menggantikan kedudukan Presiden yang lama oleh MPR menurut UUD 1945, sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas, maka secara otomatis tentunya akan terjadi kekosongan terhadap jabatan Wakil Presiden. Sehingga untuk itulah, kemudian MPR harus kembali menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden, di mana calon Wakil Presiden tersebut merupakan calon yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden. Sedangkan calon yang kemudian diusulkan oleh Presiden tersebut, haruslah terdiri dari dua calon Wakil Presiden, sehingga MPR nantinya dapat memilih dengan leluasa, yang mana mungkin menurut MPR merupakan calon yang memiliki kualitas/kapabilitas lebih, sehingga nantinya ke depan diharapkan dapat bekerja sama dengan Presiden secara harmonis. Namun, dalam hal mengangkat pengganti Wakil
I Gusti Ngurah Santika, SPd
206
Presiden, maka dibatasi pula waktu untuk MPR melakukan sidang guna memilih calon wakil presiden pengganti, yaitu enam puluh hari. Dan juga ketentuan berupa batasan waktu tersebut berlaku pula terhadap Presiden untuk secepatnya mengajukan calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih, sebagaimana dimaksudkan dalam bunyi pasal tersebut. Kemudian terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil, ternyata bisa saja terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Yang mana dikarenakan Presiden dan Wakil Presiden tersebut mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan. Oleh karena itulah, telah ditetapkan pula dalam ketentuan UUD 1945, bahwa sebagai pelaksana tugas kepresidenan secara bersama-sama yang terdiri dari tiga menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Namun, ditentukan pula batasan waktu terkait dengan pelaksana tugas kepresidenan di dalam konstitusi, yaitu tidak lebih selama tiga puluh hari. Kemudian disusul setelah terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, MPR haruslah melaksanakan sidang untuk selanjutnya memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang terdiri dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dari pemenang pemilu, yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua pada periode pemilu sebelumnya. Untuk mewujudkan ikatan batin antara jabatan dan pemangku jabatan, dirumuskanlah sumpah jabatan. Rumusan sumpah jabatan untuk Presiden, pada umumnya dicantumkan dalam undang-undang dasar. Sebelum Presiden memangku jabatannya, dia harus bersumpah terlebih dahulu, menurut agama yang dianutnya bahwa dia akan atau tidak melakukan hal-hal yang dsebutkan di dalam rumusan sumpah jabatannya (Alrasid,1993;60). Untuk sumpah jabatan seorang Presiden, maka dalam UUD 1945 kemudian telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 UUD 1945. Maka penulis berpendapat bahwa lebih tepatlah jika dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 tersebut, kemudian dikaitkan pula dengan kewenangan MPR menurut ketentuan Pasal 9 UUD 1945, yang di dalamnya terdiri dari 2 ayat, yaitu. 1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan atau Dewan Perwakilan Rakyat 2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
207
atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Dengan demikian, wewenang MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, menurut pendapat penulis merupakan suatu kewenangan untuk mengangkat sumpah atau janji di hadapan Majelis permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dan jika dalam kenyataannya tidaklah mungkin dapat dilakukan, maka untuk itu bisa saja kemudian Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan hanya disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung, asalkan sumpah atau janji tersebut dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, terkait dengan kewenangan MPR untuk mengangkat sumpah atau janji Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti apa yang telah ditentukan dalam UUD 1945, pada dasarnya adalah bersifat incidental. Dalam arti terkait dengan kewenangannya tersebut hanya diselenggarakan dalam kondisi dan waktu-waktu tertentu saja, yang pastinya akan berbeda sekali dengan kewenangan yang telah dimiliki oleh DPR dan DPD, terutama dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat rutin. Terkait dengan kewenangan MPR yang hanya bersifat insidental misalnya, tentang kewenangan MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, tentunya tidak akan pasti terkait dengan kapan waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Karena hal ini sangatlah tergantung dari kebutuhan, di samping tentunya adanya dukungan politik, sehingga perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 benar-benar dapat dilakukan kemudian. Sedangkan, dilain pihak kewenangan MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden memang bersifat tetap, yaitu setiap lima tahun. Hanya saja kewenangan MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut, ternyata hanya bersifat fakultatif. Dalam arti bisa saja bukan MPR yang kemudian melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dikarenakan pada waktu itu tidak dapat mengadakan sidang, sehingga kewenangan untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dapat saja diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, atau hanya dilangsungkan di hadapan Pimpinan MPR yang kemudian diangkat sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Asalkan saja bahwa sumpah atau janji yang kemudian diucapkan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan dengan sungguh-sungguh. Selain ditentukan tentang tempat untuk Presiden mengucapkan sumpah atau janji, maka telah ditentukan pula dalam UUD 1945 terkait dengan ada dua pilihan kepada Presiden dalam memegang jabatannya, apakah ia akan mengucapkan sumpah menurut agamanya ataukah akan menyatakan janji. Berkaitan dengan kekuatan mengikat antara sumpah dan janji terutama yang nantinya akan dinyatakan oleh Presiden, maka Alrasid
I Gusti Ngurah Santika, SPd
208
(1993;60) menyatakan bahwa yang melakukan sumpah ialah orang beragama. Jika Presiden tidak beragama, maka dia mengucapkan janji. Meskipun rumusan sumpah/janji itu isinya sama, namun, bagi kalangan orang beragama, kekuatannya tidak sama. Sumpah jabatan dinilai jauh lebih berat daripada janji. Orang lebih takut melanggar sumpah daripada melanggar janji, karena takut akan kutukan Tuhan. Lebih lanjut berkaitan dengan permasalahan dalam pengangkatan sumpah atau janji presiden yang tidak dapat dilaksanakan oleh MPR, maka dapatlah dilihat kembali dalam ketentuan Pasal 33 ayat (5) dan (6) UU No.27 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa. 5. Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. 6. Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung (kursif penulis). Kemudian lebih lanjut, terkait dengan adanya kewenangan daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang selanjutnya tercantum dalam ketentuan ayat (3) Pasal 3 UUD 1945, yang dinyatakan bahwa Majelis Pemusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (kursif penulis). Untuk dapat lebih memahami terkait dengan kewenangan MPR, seperti tersebut di atas, maka untuk itu kita perlu sekali lagi menyimak kembali proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 tersebut. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas terdapat kata hanya dapat memberhentikan dan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kita tentunya akan menengok terlebih dahulu, tentang tata cara (prosedur) terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang telah ditentukan secara tegas dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dapatlah kita temukan terkait dengan tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan, tepatnya dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Hal mana di sini kita hanya akan menyinggungnya sedikit saja, karena nantinya akan penulis jelaskan kembali dalam pembahasan selanjutnya, terutama dalam Bab III UUD 1945 yang mengatur tentang Presiden dan Wakil Presiden. Dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 pada intinya mengatur prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang pada dasarnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
209
menyatakan, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang kemudian jika ada usul dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang ternyata usul tersebut merupakan bukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar telah melakukan tindak pidana tertentu, yang sebelumnya telah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun, untuk membuktikan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945, serta tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana didakwakan lewat pendapatnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka perlulah diuji terlebih dahulu kebenarannya oleh sebuah lembaga peradilan konstitusi (constitutional court) yaitu Mahkamah Konstitusi. Sehingga berdasarkan putusannya tersebut kemudian benar-benar dapat menjadi pertimbangan MPR, untuk melakukan tugasnya seperti apa yang diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu dalam rangka memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penulis mengatakan dapat menjadi pertimbangan MPR, hal mana dikarenakan dalam ketentuan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945, ternyata ditemukan kata dapat, sehingga menurut kata itulah kemudian penulis mengambil kesimpulan bahwa walaupun ada putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang kesalahan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, maka MPR tentunya dalam hal ini boleh saja memberhentikan atau boleh juga dengan tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. Dengan demikian, semua keputusan terkait dengan pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden akan sangatlah tergantung pada kehendak sepihak dari MPR. Namun, jika dicermati kembali dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 dapatlah ditemukan suatu kata yang berbunyi hanya dapat memberhentikan menurut UndangUndang Dasar dan dapat dilihat kembali dalam ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, dapat ditemukan kata berbunyi hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan, sehingga untuk itu penulis berpendapat bahwa MPR tidaklah berwenang untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden jika ternyata pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang mana merupakan usul berupa dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaraan hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden ternyata tidak terbukti, atau dengan kata lain bahwa
I Gusti Ngurah Santika, SPd
210
Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersalah terhadap dakwaan yang berupa suatu pendapat yang sebelumnya diajukan oleh DPR. Sehingga proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat lagi diajukan oleh DPR ke MPR untuk selanjutnya diputuskan, karena terhenti oleh adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, yang menolak pendapat DPR seperti tersebut di atas. Berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara final merupakan suatu kewenangan MPR, bukanlah kewenangan MK sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Yang kemudian ditegaskan kembali dalam UU No. 27 Tahun 2009, tepatnya dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) yang berbunyi. 1. Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya. 2. Dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya (kursif penulis). Oleh karena itu, walaupun dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang membuktikan tentang pendapat dari DPR mengenai dugaan kesalahan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, maka keputusan terakhir tetaplah berada di tangan MPR. Jika MPR kemudian memutuskan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka tentunya Presiden dan/atau Wakil Presiden akan berhenti seketika itu dari jabatannya, tetapi jika dalam kenyataannya MPR ttidak memutuskan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden akan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya. Berkaitan dengan kewenangan MPR dalam melaksanakan tugasnya-tugasnya maka diperlulah untuk selanjutnya mengadakan sidang-sidang, yang dilaksanakan oleh MPR, seperti apa yang kemudian diamanatkan ataupun diberikan oleh UUD 1945. Maka dapatlah terlihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Ternyata walaupun dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, tetapi terkait dengan ketentuan ayat (2) dari Pasal 2 UUD 1945 ini, tidaklah kemudian mengalami suatu perubahan, maka dapat dipastikan bahwa makna yang terkandung di dalamnya pun pasti masih sama, seperti dahulu ketika sebelum UUD 1945 diamandemen. Oleh karena itu, perlulah kemudian dikutipkan bunyi daripada Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, yang pada dasarnya di dalamnya dinyatakan bahwa MPR adalah.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
211
Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikit-sedikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa. 2. Presiden Dan Wakil Presiden Hamidi dan Lutfi (2010;118) menyatakan lembaga Kepresidenan merupakan sebuah institusi yang terdiri atas Presiden bersama dengan Wakil Presiden serta sejumlah aparat pemerintah yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Aparat pemerintah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pengertian pemerintah yang memiliki arti sempit, karena hanya menyangkut Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menteri sebagai pembantu Presiden, yang kemudian biasa disebut dengan pejabat eksekutif yang berada pada tingkat pusat. Dikarenakan selain adanya pengertian pemerintah/eksekutif dalam arti yang sempit sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas, dalam kenyataanya terdapat juga pengertian eksekutif dalam arti luas. Badan eksekutif dalam arti luas tidak hanya Presiden beserta pembantu-pembantunya, yang dalam hal ini adalah menteri-menteri yang mendampinginya. Karena di samping itu menurut Budiardjo (2008;295), bahwa pengertian eksekutif dalam arti luas merupakan badan yang juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Sehingga, dapat dikatakan bahwa badan eksekutif dalam arti luas tidak hanya menyangkut Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menterinya saja, melainkan juga meliputi seluruh pegawai negeri sipil dan militer sebagaimana dimaksudkan sebelumnya oleh Mirriam Budiardjo. Hal mana tentunya akan berbeda dengan pengertian yang kemudian diberikan oleh Mahmud MD (2001;66) yang menyatakan bahwa pemerintah dalam arti sempit (yang disebut berstuur) hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang biasa dilakukan oleh Kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dengan demikian, Mahmud MD memberikan pengertian pemerintah dalam arti sempit, yang pada dasarnya juga meliputi pegawai negeri dan militer sebagaimana dimaksudkan sebelumnya oleh Budiardjo yang dapat dikatakan merupakan tambahan bagi pengertian eksekutif dalam arti yang luas. Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dirumuskan bahwa: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan salah satu pasal yang sebelumnya tidak dilakukan perubahan oleh MPR. Bahkan, Badan Pekerja MPR yang melakukan perubahan pada waktu itu memandang ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
I Gusti Ngurah Santika, SPd
212
tidaklah perlu untuk dirubah, dikarenakan memang tidak ada hubungan antara otoriterisme yang dibangun dalam pemerintahan selama ini dengan adanya pasal tersebut. Dengan demikian, tidaklah perlu untuk dipertimbangkan dengan mengadakan perubahan terhadap ketentuan tersebut, sebagaimana dimaksudkan di atas, hingga pada akhirnya terkait dengan masalah tersebut semua anggota Badan Pekerja menyepakatinya. Kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, adalah kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif, yang merupakan kewenangan Presiden dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan tertinggi, sebagai wujud satu kesatuan daripada kedudukannya, yaitu di samping sebagai kepala pemerintahan juga merupakan kepala negara. Dengan demikian, dapatlah kemudian dikatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tersebut memiliki makna yang sama, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Dengan adanya pasal tersebut, maka untuk selanjutnya Presiden dapat saja mengeluarkan peraturan-peraturan serta penetapanpenetapan yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan, bahwa kekuasaaan pemerintahan dalam arti dapat membentuk peraturan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam arti bahwa pelaksanaan (uitvoering), dapat berarti pengeluaran penetapan-penetapan atau berupa perbuatan-perbuatan nyata lainnya atau berupa pengeluaran peraturan-peraturan lebih lanjut (gedelegeerde wetgeving). Hal ini tentunya adalah sesuai dengan Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 tersebut, yang berbunyi. Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undangundang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair) (kursif penulis). Namun, berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Ghaffur (2011;77) menyatakan bahwa kata-kata menurut Undang-Undang Dasar berarti wewenang diatur di dalam UUD sehingga pembatasan wewenang tersebut terletak sesuai apa yang tertulis di dalam UUD tersebut. Meskipun begitu, karena Indonesia adalah negara hukum, maka Presiden juga harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang lain. Bahkan menurut Hamzah (2012;190) bahwa eksekutif pada intinya dipilih oleh rakyat untuk memerintah menurut undang-undang, bukan memerintah tanpa undang-undang seperti diktaktor. Dengan demikian, UUD 1945 dan undang-undang serta peraturan lainnya merupakan dasar daripada tindakan pemerintahan, dalam melaksanakan segala tugas yang sebelumnya telah dibebankan. UUD 1945 menjadi pembatas pemerintah dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
213
menjalankan tugasnya, maka tidak benarlah jika kemudian pemerintah berkehendak untuk melangkahi UUD 1945, apalagi tindakannya nyata-nyata melanggar UUD 1945, yang mana tentunya akan merugikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya, berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presidenlah yang memegang kekuasaan pemerintahan, kemudian akan terlihat bahwa Presiden memegang kekuasaan yang sangat besar. Hal tersebut dikatakan, karena terdapat kata pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut, memiliki makna yang menurut pendapat penulis adalah jamak. Menurut Soemantri (1992;45) bahwa pemerintah mempunyai dua macam pengertian, pertama, dalam arti luas, yang meliputi semua cabang kekuasaan dalam negara, yang terbentuk dalam alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) dan kedua, dalam arti sempit, yang hanya mengenai satu cabang kekuasaan saja. Apabila dilihat dari teori yang diberikan oleh Van Vollen Hoven, pengertian pemerintahan (regering) bisa berartikan sebagai lembaga (overhead) dapat pula sebagai suatu fungsi. Pemerintahan dalam arti luas terdiri atas empat fungsi, yaitu ketataprajaan (bestuur), pengaturan (regeling), keamanan/kepolisian (politie), dan peradilan (rechtpraak) di mana fungsi yang terakhir ini kemudian dipisahkan karena adanya wawasan negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) (Indrati,2007;131). Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan kekuasaan eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya yang termasuk legislatif dan yudikatif (Nugroho,2011;13). Dengan demikian, seperti apa yang sebelumnya telah dinyatakan di atas oleh para ahli, Mahmud (2001;66) menyatakan mengenai hal yang sama mengenai pengertian pemerintah dalam arti luas, yang menurutnya meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan pemerintah dalam arti luas ini diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut regering. Sedangkan menurut Attamimi (1990;114) pemerintahan dalam arti luas, meliputi segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri. Sedangkan dalam arti sempit ialah hanya menjalankan tugas eksekutif saja. Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif (Manan dan Magnar,1997;158-159). Terkait dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
214
pengertian pemerintahan, bahkan Kusnardi dan Sarigih (2008;113) menyatakan bahwa pemerintah harus diartikan luas yang mencakup semua badan-badan negara. Sehingga, menurut Ridwan HR (2011;30) bahwa pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Namun, terkait dengan pemaparan kali ini hanya akan dibahas pengertian pemerintahan dalam arti sempit, yang tentunya hanya meliputi tugas dan kewenangan presiden sebagai kepala negara sekaligus juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dimaksudkan oleh UUD 1945. Walaupun jika kita perhatikan, maka dapatlah kemudian dikatakan bahwa Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi menurut UUD 1945, yang menjalankan seluruh tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas, yang bisa menyangkut berbagai tugas, seperti ketataprajaan, keamanan/kepolisian, dan pengaturan. Namun, tugas utama yang dibebankan kepadanya adalah pemerintahan dalam arti eksekutif saja, sedangkan untuk tugas-tugas lainnya, adalah tugas tambahan yang biasanya diberikan kepadanya karena terkait dengan kedudukannya sebagai kepala negara. Hal ini kemudian akan terlihat lebih jelas lagi, apabila negara tersebut merupakan negara yang pada dasarnya menganut sistem pemerintahan parlementer. Selain itu, pasal tersebut juga menunjukan adanya pengertian Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial, bukan sistem pemerintahan yang menganut parlementer. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak diperlukan adanya pembedaan atau tidak perlunya untuk kemudian dibedakan antara presiden sebagai kepala negara dan presiden selaku kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak mengatur tentang kedudukan kepala negara (head of government) atau chief executive. Hal ini tentu akan berbeda maknanya jika UUD 1945, menganut sistem pemerintahan parlementer, sehingga dipandang perlu untuk memisahkan jabatan antara Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jika kita telusuri kembali dalam sejarahnya, maka penjelasan UUD 1945 yang menurut banyak ahli ternyata dibuat oleh Soepomo kemudian, dan dari sanalah kita dapat melihat adanya pembedaan yang dituliskan secara eksplisit, terkait dengan Presiden yang di samping dinyatakan sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Penjelasan tentang UUD 1945 itu sendiri diumumkan resmi dalam Berita Republik Tahun II No. 7, 15 Februari 1946 dan kemudian dijadikan lampiran tak terpisahkan dengan naskah UUD 1945 oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 (Darmodihardjo,dkk,1991;155). Dalam Penjelasan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
215
tersebut, istilah ini dipakai pada waktu itu adalah untuk menjelaskan kedudukan Presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945 yang merupakan kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of government) sekaligus. Untuk lebih lebih memperjelas kedudukan penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, bahwa banyaklah orang yang mungkin mengira bahwa UUD 1945 yang sebenarnya merupakan karya besar dari BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sudah langsung dilengkapi dengan Penjelasannya. Dapat diketahui bahwa Penjelasan UUD 1945 sebagaimana tercantum di belakang Batang Tubuh UUD 1945 seperti sekarang (sebelum perubahan) baru dicantumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, 15 Februari 1946. Penjelasan yang dicantumkan dalam Berita Republik Indonesia tersebut ditulis oleh Soepomo yang disarikan dari pembahasan UUD dalam forum BPUPKI. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh, dengan di dahului disahkannya pembukaan dan selanjutnya diikuti dengan disahkannya batang tubuhnya (pasal-pasal). Sebagai akibat diakuinya adanya dua kualitas kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan itu, timbul kebutuhan yuridis untuk membedakan keduanya dalam pengaturan mengenai hal-hal yang lebih teknis dan operasional. Misalnya, dibayangkan bahwa Presiden perlu dibantu oleh sekretaris dalam kualitasnya sebagai kepala negara, dan sekretaris yang lain lagi untuk membantu dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan. Inilah sebabnya muncul ide untuk membedakan antara sekretaris negara dengan sekretaris kabinet disepanjang sejarah masa lalu. Namun, dalam praktek adanya kedua jabatan ini kadang-kadang menimbulkan permasalahan. Hal ini tidak lain disebabkan karena, pemangku kedua jabatan ini sering bersaing dalam melayani pimpinan. Yang dalam hal ini menurut Asshiddiqie (2006;127) tidaklah diperlukan adanya suatu pembedaan sebagaimana dimaksudkan di atas, dikarenakan bahwa: Sebenarnya perbedaan-perbedaan semacam itu tidaklah bersifat riil, melainkan hanya perbedaan di atas kertas, yang hanya ada dalam diskourse wacana. Kalaupun dianggap penting, paling-paling untuk kebutuhan hal-hal yang bersifat protokoler yang biasanya berlaku dalam forum-forum pergaulan antar negara, khususnya terkait dengan kepala negara dan/atau kepala pemerintahan. Misalnya, dalam pertemuan di forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), kerap diadakan pertemuan khusus antar kepala negara, berarti yang hadir adalah para presiden dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
216
para raja atau ratu. Tetapi jika pertemuan yang diadakan adalah antar kepala pemerintahan, maka yang hadir adalah Presiden dan para perdana menteri (Prime Ministers), sedangkan raja dan ratu sebagai kepala negara tidak diundang. Pembedaan yang menjadi penting, karena banyak negara yang memang menganut praktek yang memisahkan antara kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu, yaitu khususnya negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Namun, di lingkungan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil murni, memang tidak diperlukan pembedaan dan apabila pemisahan antara pengertian kepala negara dan kepala pemerintahan itu. Yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan tidak dapat dipisahkan dalam sistem pemerintahan presidensiil. Hal tidak mungkin dilakukan pembedaan dalam jenis surat keputusan presiden dalam dua macam kedudukan. Keputusan Presiden selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan tidak relevan untuk dibedakan. Pembedaan dan apalagi pemisahan keduanya hanya akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam praktek di lapangan yang justru dapat menimbulkan kekisruhan dan bahkan kekacauan administrasi atau menggangu tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan (Asshiddiqie,2006;128). Selain pengaturan tentang Presiden ternyata di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, diatur juga mengenai satu orang Wakil Presiden yang nantinya akan bertugas untuk membantu Presiden, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti apa yang kemudian dinyatakan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa : Dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (kursif penulis). Kata dibantu tersebut tidaklah sama maknanya dengan kata dibantu seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 17 UUD 1945, dikarenakan kedudukan Wakil Presiden adalah lebih tinggi daripada kedudukan menteri-menteri dalam kabinet. Hal ini dikarenakan, secara konstitusional Wakil Presiden memiliki kedudukan yang tentunya berbeda dengan menteri-menteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUD 1945. Terutama berkaitan dengan tingkat legitimasi antara Wakil Presiden dengan menterimenteri dalam kabinet. Secara konstitusional, Wakil Presiden merupakan satu pasangan dengan Presiden pada saat pemilihan umum, pada dasarnya memiliki legitimasi lebih tinggi dari menteri-menteri, karena ia dipilih oleh rakyat secara langsung. Sedangkan untuk menteri yang merupakan pembantu Presiden dan tentunya pada saat-saat tertentu, dimana Presiden tidaklah dapat melaksanakan tugas, entah karena adanya kunjungan ke luar negeri
I Gusti Ngurah Santika, SPd
217
dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh hukum ataupun karena tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan seterusnya. Maka untuk itu, Wakil Presidenlah yang kemudian menggantikan posisi Presiden untuk sementara waktu atau mengganti kedudukannya secara permanen sampai habis masa jabatannya. Dengan demikian tentunya menteri-menteri tersebut harus tunduk dan patuh pada perintah Wakil Presiden yang sebelumnya telah mendapatkan mandat untuk menjalankan tugas-tugas Presiden, walaupun bersifat sementara waktu atau memang tidak dapat lagi menjalankan tugas pemerintahannya, seperti apa yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Selanjutnya berkaitan dengan tugas Presiden dalam bidang pembentukan undangundanga, dapatlah dilihat kemudian dalam ketentuan Pasal 5 UUD 1945, yang disebutkan antara lain sebagai berikut. 1. Presiden berhak mengajukan Perwakilan Rakyat. rancangan undang-undang kepada Dewan
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya (kursif penulis). Perubahan pasal ini telah memindahkan secara tidak langsung titik berat daripada kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, kemudian beralih ke tangan DPR. Pemberdayaan DPR tidak menyebabkan DPR lebih kuat dibandingkan Presiden, karena kedua lembaga negara tersebut berada dalam kedudukan yang seimbang/setara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Berkaitan dengan kekuasaannya Presiden dalam pembentukan undang-undang Sebelum UUD 1945 diamandemen, telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang bunyinya, yaitu Presiden memegang kekuasan membentuk undang-undang(kursif penulis). Dengan demikian, pada waktu itu telah ditentukan bahwa Presiden selain memegang kekuasaan pemerintahan, sebagaimana kemudian dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden juga menurut UUD 1945 sebelum diamandemen, ternyata ditentukan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, seperti bunyi dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Inilah yang menurut pendapat banyak ahli merupakan salah satu sumber penyebab daripada otoriternya tindakan Presiden, seperti yang pernah dialami pada masa Orde Baru terutama dalam menjalankan pemerintahan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Kemudian ketentuan tentang Presiden yang memegang kekuasaan membentuk undangundang, selama perjalanannya ternyata banyak disalahgunakan oleh Presiden, sehingga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
218
seolah-olah tindakannya dapat dibenarkan, jika kemudian dilihat dari sudut konstitusional, walaupun ketika itu sebenarnya banyaklah undang-undang yang dibentuk sebelumnya ternyata bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dominannya kedudukan Presiden dalam pembuatan undang-undang, dengan ditambah flexible-nya Undang-Undang Dasar, yang mana tentunya membutuhkan pengaturan lebih lanjut, terutama lewat atribusi dalam bentuk undang-undang, menyebabkan isi undangundang tersebut kebanyakan merupakan pencerminan kehendak sepihak daripada sang penguasa, yaitu Presiden. Sehingga, banyak yang kemudian mengatakan bahwa dengan besarnya kekuasaan yang diberikan kepada seorang Presiden oleh Undang-Undang Dasar 1945, telah menyebabkan pula sistem pemerintahan yang dianut pada waktu itu, adalah executive heavy. Dengan demikian, terlihat ketentuan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum diamandemen,, telah memberikan fungsi ganda kepada Presiden, atau dengan kata lain, Presiden sebagai satu organ ternyata ditentukan dalam UUD 1945 memiliki dua fungsi sekaligus. Padahal fungsi Presiden yang merupakan lembaga eksekutif, seharusnya hanya memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Namun, oleh undang-undang dasar itu sendiri, telah memperluas pengertian pemerintahan menurut undang-undang dasar, dengan menambahkan kepada Presiden berupa tugas, untuk memegang kekuasaan pembentukan undang-undang yang seharusnya dipegang oleh DPR. Namun, dengan adanya perubahan terhadap ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tersebut, telah menyebabkan pula terjadinya pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Dengan demikian, pemegang utama (primer) kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-undang adalah DPR, sedangkan Presiden hanyalah pemegang kekuasaan sekunder (Widarsono,2002;18). Peletakan kembali fungsi kelembagaan negara adalah disesuaikan dengan kedudukan lembaga negara tersebut, yang memang seharusnya ditentukan untuk memegang fungsi tersebut. Adanya perubahan tersebut, merupakan suatu kebijakan yang dapat dinilai sangatlah tepat dan hal ini sudah dilakukan oleh MPR, terutama pada saat perubahan pertama. Perubahan pertama tersebut mengagendakan untuk mengembalikan fungsi kewenangan yang seharusnya dipegang oleh kembaga negara tersebut, atau lebih konkretnya adalah bertujuan untuk mengurangi kekuasaan Presiden, terutama berkaitan dengan kekuasaannya di dalam bidang pembentukan undang-undang. Sehingga, nantinya diharapkan undang-undang yang kemudian dibentuk, memang sungguh-sungguh merupakan kehendak rakyat yang berdaulat. Semua itu tidak lain, dikarenakan undang-undang tersebut benar-benar dibuat oleh wakil-wakil rakyat sendiri,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
219
sehingga dengan demikian undang-undang itu merupakan produk dari rakyat yang berdaulat. Namun, dilain pihak, dengan dirubahnya ketentuan pasal tersebut, tidaklah berarti kemudian menghapus sama sekali keterlibatan Presiden dalam bidang pembentukan undang-undang, dikarenakan Presiden ternyata juga diberikan berupa hak untuk kemudian mengajukan rancangan undang-undang. Dengan adanya hak yang diberikan oleh UUD 1945, dalam hal mengajukan rancangan undang-undang oleh Presiden kepada DPR, berarti telah memberikan kesempatan pula kepada pemerintah untuk mengajukan hal-hal, yang sebelumnya dibutuhkan oleh pemerintah untuk kemudian dijadikan dasar dalam melakukan tugasnya, terutama berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, yang tentunya perlu diatur kembali dalam bentuk undang-undang. Sebenarnya tentu banyak pertimbangan, yang sebetulnya dijadikan dasar oleh MPR, untuk tidak menghapus sama sekali keterlibatan Presiden dalam bidang pembentukan undang-undang. Dapatlah dikatakan bahwa, dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik sumber daya manusia (tenaga ahli) dan perlengkapan, serta merupakan ujung tombak negara terutama dalam mewujudkan tujuan nasional, yaitu untuk menyejahterakan rakyat, serta tercapainya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, maka dipandang perlu diberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Bahkan, telah ditentukan dalam ketentuan ayat (2) dari Pasal 5 UUD 1945 bahwa, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah itu merupakan bentuk delegated legislation atau kewenangan yang di delegasikan oleh principal legislator atau pembentuk undang-undang kepada Presiden selaku kepala pemerintahan yang akan menjalankan (eksekutif) undang-undang yang bersangkutan (Asshiddiqie,2012;167). Bahkan terkait dengan adanya ketentuan tersebut, kemudian Kelsen (2011;361) menyatakan pendapatnya bahwa jika kita berbicara tentang eksekutif, yang berarti pelaksanaan, kita harus bertanya apakah yang dillaksanakannya. Tidak ada jawaban lain kecuali pernyataan bahwa yang dilaksanakan itu adalah norma-norma umum, konstitusi, dan hukum-hukum yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dimaknai sebagai kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kemauan negara dan pelaksanaan undang-undang (ICCE UIN,2010;72). Hal ini karenakan, untuk dapat dijalankannya sebuah undang-undang, maka perlulah diatur kembali dalam bentuk peraturan yang berada di bawah posisi undang-undang tersebut, agar kemudian lebih teknis sehingga undang-undang dapat operasionalkan di lapangan. Dan tentunya kewenangan untuk membentuk peraturan di bawah undang-undang tersebut terletak pada lembaga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
220
eksekutif, atau yang lebih konkretnya untuk Indonesia menurut UUD 1945 adalah terletak pada tangan Presiden, yang berkedudukan pula sebagai kepala administrasi tertinggi. Maka penulis mengutip pendapat Situmorang dan Sudibyo (1992;17) yang menyatakan bahwa administrasi negara memandang undang-undang itu sebagai rumusan dari kehendakkehendak negara tersebut, yang wajib dipenuhi atau realisasi oleh administrasi negara. Dikarenakan undang-undang bersifat umum-abstrak, yang untuk itu, perlulah kemudian direalisasikan kembali dalam bentuk peraturan pemerintah, sebagai bentuk peraturan yang berada tepat di bawah undang-undang, sehingga dapatlah kemudian untuk dilaksanakan di lapangan. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapatlah kemudian dikatakan jelas sekali fungsi dan peranan daripada lembaga pemerintahan, yang dalam kenyataannya bukan saja melaksanakan kebijaksanaan negara, tetapi juga berperan dalam merumuskan kebijaksanaan tersebut. Peranan kembar yang dimainkan oleh lembaga pemerintahan tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya peranan administrasi negara (Islamy,2004;9). Berkaitan Presiden yang juga memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan Undang-Undang sebagimana mestinya. Kata sebagaimana mestinya artinya adalah materi dalam muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dengan undang-undang yang bersangkutan. Dari penjelasan ini timbul penafsiran bahwa sekiranya tidak diperintahkan secara eksplisit pun undang-undang, PP tetap dapat dikeluarkan oleh Pemerintah asalkan materinya tidak bertentangan dengan undang-undang, dan asalkan hal itu memang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang timbul dalam praktik untuk dimaksud menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Asshiddiqie,2006;216). Dengan kata lain bahwa pemerintah menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka dengan bertitik tolak dari situasi-situasi dan kondisi-kondisi tertentu, bukan atas dasar doktrin umum (Barros,1984;165). Dalam hubungan dengan pendelegasian kewenangan itu, kadang-kadang timbul permasalahan, misalnya kewenangan yang didelegasikan tersebut disalahgunakan oleh pemerintah. Jika umpamanya, materi yang diatur dalam Peraturan pemerintah itu berlebihan atau dengan kata laintidak menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dikarenakan Peraturan Pemerintah tersebut mengurangi atau menambah materi yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga berakibat mengubah materi undangundang yang dimaksud. Maka, dalam UUD 1945 sudah dengan jelas tercantum tentang mekanisme yang dapat dilakukan untuk menguji Peraturan Pemerintah tersebut, apakah sesuai dengan undang-undang yang dimaksud. Mekanisme pengujian peraturan di bawah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
221
undang-undang berada pada Mahkamah Agung. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menentukan, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang (Asshiddiqie,2006). Kemudian berkaitan dengan kekuasaan legislatif yang juga dimiliki oleh Presiden, seperti dalam ketentuan UUD 1945 antara lain disebutkan, bahwa Presiden dan DPR mempunyai wewenang yang sama, untuk membahas setiap rancangan untuk kemudian disetujui bersama agar menjadi undang-undang (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama). Dengan begitu, dapatlah kemudian dikatakan bahwa Presiden masih memiliki kewenangan dalam bidang legislatif, terutama dalam bidang pembentukan undang-undang. Yang berarti tidak hanya dalam bentuk pengajuan rancangan undangundang yang merupakan haknya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, namun ternyata juga ditentukan keterlibatan Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama-sama dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Untuk lebih jelasnya, dapatlah kemudian dilihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (kursif penulis). Jadi, untuk dapat sebuah rancangan undang-undang kemudian menjadi undang-undang haruslah terlebih dulu adanya persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, sebagai dua lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Bahkan dinyatakan di di dalamnya, jika seandainya suatu rancangan undang-undang yang sebelumnya tidak mendapat persetujuan bersama, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan ayat (2) dari Pasal 20 UUD 1945 tersebut, maka rancangan undang-undang yang sebelumnya telah dibahas tersebut, tidaklah boleh diajukan kembali untuk dibahas terutama sebelum berakhirnya periode persidangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa itu. Pendapat tersebut dapatlah kita temukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 secara lengkap bunyinya, yaitu Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Selain ketentuan tersebut ternyata berkaitan dengan pembentukan undang-undang dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dengan demikian, untuk berlakunya rancangan undang-undang atau agar rancangan undang-undang tersebut dapat mengikat umum, maka diperlukanlah pengesahan daripada Presiden, berupa tanda tangannya sebagai
I Gusti Ngurah Santika, SPd
222
tanda persetujuan untuk kemudian berlakunya undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut sering pula terlihat dalam sistem pemerintahan yang menganut Parlementer, di mana suatu rancangan undang-undang yang sebelumnya telah dibahas oleh menteri bersama dengan parlemen, kemudian harus kembali disahkan oleh raja, agar rancangan undang-undang tersebut dapat menjadi undang-undang sehingga berlaku, bahkan mengikat umum. Namun, untuk UUD 1945, telah menentukan bahwa walaupun tanpa adanya suatu pengesahan rancangan undang-undang oleh Presiden, maka rancangan undang-undang yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama tersebut, akan sah menjadi undangundang, dalam tempo waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut telah mendapatkan persetujuan bersama, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Bunyi dari pasal tersebut, yaitu. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan (kursif penulis). Terkait dengan tugasnya dalam bidang pembentukan undang-undang, maka selanjutnya juga ditentukan dalam UUD 1945, bahwa Presiden ternyata berwenang untuk mengeluarkan Perpu. Ketentuan ini dapat pula kita ketahui dari dalam ketentuan Pasal 22 UUD 1945, yang di dalamnya terdiri dari 3 ayat. Secara lengkap ketentuan tersebut berbunyi, yaitu. 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Dalam ketentuan Pasal 22 UUD 1945, merupakan salah satu pasal yang sebelumnya tidak mengalami perubahan, sehingga memiliki makna yang sama pula dengan sebelum adanya perubahan terhadap UUD 1945. Pertimbangan daripada para pembentuk UUD 1945, untuk kemudian mencantumkan ketentuan ini dalam UUD 1945, dapatlah kita ketahui dan dapat kemudian ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus. Yang pada dasarnya menyatakan bahwa.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
223
Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya ketentuan ini, maka pemerintah dapat membuat suatu peraturan yang secara meteriil (isinya) memiliki kedudukan sama dengan undang-undang, sebagaimana dimaksudkan oleh Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus. Dan tentunya berkaitan dengan pengertian ini sampai sekarang pun masih sama dengan yang dulu. Tidak lain dikarenakan bahwa dalam ketentuan Pasal 22 UUD 1945 tidaklah mengalami perubahan, yang berarti maknanya pun masih sama pula seperti sebelum adanya perubahan terhadap UUD 1945. Kemudian Indrati (2007;215) berpendapat bahwa fungsi Perpu adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh (sebutan sebelum perubahan) UUD 1945, pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya, pengaturan di bidang materi konstitusi. Namun, disertai dengan adanya catatan bahwa dari keempat fungsi daripada Perpu di atas, ternyata berkaitan dengan ketentuan untuk melaksanakan perintah ketetapan dari MPR adalah sudah tidak lagi bisa untuk dilakukan. Karena pada dasarnya MPR sendiri tidak lagi berwenang untuk mengeluarkan suatu ketetapan yang bersifat mengatur, terutama setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945. Pengeluaran perpu oleh Presiden merupakan tafsiran Presiden secara sepihak terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa, sehingga dengan demikian menurut Presiden, dipandang perlu, untuk segera diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang memang tidaklah kemudian dikehendaki. Namun, yang memiliki hak untuk selanjutnya menilai secara objektif terhadap tafsiran Presiden mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat. Terbukti setelah ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut oleh Presiden, haruslah segera dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan berikutnya. Jika, nantinya Dewan Perwakilan Rakyat ternyata kemudian dalam keputusannya menyatakan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagaimana dimaksudkan oleh Presiden, yang kemudian disusul dengan mengeluarkan peraturan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
224
pemerintah pengganti undang-undang, ternyata dibenarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut akan menjadi undangundang definitif. Sedangkan apabila ternyata DPR kemudian menolak untuk menyetujui dengan mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut haruslah dicabut. Pada dasarnya, Perpu itu mempunyai derajat yang sama dengan Undang-Undang, maka untuk itu DPR haruslah secara aktif mengawasi baik penetapan, maupun pelaksanaan Perpu tersebut di lapangan, janganlah sampai penetapan Perpu tersebut bersifat eksesif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatar belakangi kelahirannya. Dengan demikian, Perpu itu harus dijadikan objek pengawasan yang sangat ketat oleh DPR, sesuai dengan tugasnya terutama dibidang pengawasan termasuk dalam bidang pembentukan dan pelaksanaan undang-undang. Dalam UU No.12 Tahun 2011, juga diatur kembali berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimanatkan oleh UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 22. Kemudian adanya ketentuan Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 yang di dalamnya terdiri dari 5 ayat. Bunyi dari pasal tersebut di atas selengkapnya. 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. 2. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan UndangUndang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. 3. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. 5. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. 6. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
225
7. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 8. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) (kursif penulis). Memang dalam berbagai hal dapat saja terjadi suatu peristiwa yang memang tidak dapat diduga-duga sebelumnya, bahwasanya Presiden dalam kenyataannya memerlukan tindakan yang cepat, tetapi ternyata belumlah ada pengaturannya khususnya dalam bentuk undang-undang. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidaklah dapat bertindak leluasa untuk kemudian mengambil tindakan yang cepat untuk menanggapi situasi dan kondisi tersebut. Sedangkan bisa saja, ketika hanya menggunakan situasi seperti biasa sebagai pedoman dalam pembentukan dasar hukum bagi tindakan pemerintah, seperti misalnya dalam bentuk undang-undang. Sehingga mungkin saja akan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan untuk menaggapi situasi tersebut, tidaklah dapat ditunda-tunda lagi, apalagi yang paling penting adalah berkaitan dengan keselamatan rakyat ataupun yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, yang pada dasarnya memang merupakan tugas utama pemerintah. Dalam pertimbangan tersebut, selanjutnya mengingat kebutuhan masyarakat yang makin lama makin kompleks untuk segera dipenuhi, sedangkan pembuatan undang-undang lambat dan anggotanya terdiri dari orang-orang amatir, maka dalam hal ini pemerintah tidak dapat menunggu pembuat undang-undang dalam menyelenggarakan kepentingan umum (Kusnardi dan Sarigih,2008;93). Adanya ketentuan ini, merupakan satu konsekuensi dari dalam peraturan perundang-undangan sendiri yang mengamanatkan bahwa sebagai suatu negara dalam bentuk Welfare state (negara kesejahteraan, negara hukum yang dinamis) dengan Freies Ermessen nya yang menurut E. Utrecht mengundang konsekuensi sendiri dalam bidang perundang-undangan, yakni diberikannya kewenangan bagi pemerintahan untuk membuat peraturan perundangan baik atas inisiatif sendiri maupun atas delegasi yang diterimanya dari UUD serta menafsirkan isi peraturan yang bersifat enunsiatif (enumeratif) (Marbun dan Mahmud MD,2000;53-54). Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur) (Ridwan HR,2011;171). Karena tidaklah mungkin dapat di setiap situasi untuk kemudian ditangani dengan prosedur yang sama. Oleh karena itu, derajat yang tepat dari delegate discreation akan berbeda-beda menurut berbagai kondisi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
226
dalam dan luar yang dihadapi sebuah organisasi dari waktu ke waktu (Fukuyama,2005;64). Sehingga dengan demikian, dapatlah selanjutnya dikatakan bahwa kondisi merupakan prasyarat utama dalam mengambil tindakan, khususnya berkaitan dengan pemenuhan kepentingan umum. Itu pulalah sebabnya mengapa negara administratif itu selalu dihubung-hubungkan dengan welfare state oleh karena suatu pemerintahan harus berusaha, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas, wewenang dan tanggungjawabnya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Siagian,1985;104). Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah mewakili dan mengurus kepentingan umum (Kusumaatmadja dan Sidharta,2000;17). Dengan kata yang lain, dapat dikatakan bahwa Presiden memiliki salah satu tugas, yaitu pembentukan hukum (rechtcvorming) merupakan penentuan kaidah abstrak yang berlaku umum (Sokanto dan Mamudji,2009;5). Memang ada baik apabila peranan pemerintah yang bertambah besar dalam penciptaan Welfare State yang tentunya juga memerlukan kelincahan yang lebih besar jika dibandingkan hanya dengan suatu negara di mana pemerintahnya terutama bersikap sebagai polisi dan hanya bertindak atas permintaan perseorangan atau apabila ada kepentingan yang dilanggar. Akan tetapi dilain pihak, terhadap kebebasan bertindak dan mengatur bertambah besar dalam negara-negara ini, perlu dipikirkan cara-cara yang tepat agar dapat dipelihara keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan warga negara (Lopa dan Hamzah,1991;18). Lebih lanjut terkait dengan adanya ketentuan tersebut di atas, dapat kemudian dilihat kembali dari ketentuan UUD 1945, tepatnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945, yang dalam hal ini menurut pendapat Asshiddiqie (2006;80-83), bahwa : 1. Peraturan tersebut peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, yang berarti bahwa bentuknya adalah peraturan pemerintah (PP) sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Pasal 5 ayat (2) ini menyatakan,Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jika biasanya bentuk Peraturan Pemerintah itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka dalam keadaan kegentingan yang memaksa bentuk Peraturan Pemerintah itu dapat dipakai untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang semestinya dituangkan dalam bentuk undang-undang dan untuk menggantikan undang-undang. 2. Pada pokoknya, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan oleh UUD 1945. Namun, dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
227
praktek selama ini, peraturan pemerintah yang demikian itu lazim dinamakan sebagai Peraturan Pemerintah (tanpa sebagai) Pengganti Undang-Undang atau disingkat PERPU atau biasa juga ditulis perpu 3. Perpu tersebut pada pokoknya hanya dapat ditetapkan oleh Presiden apabila persyaratan kegentingan yang memaksa itu terpenuhi sebagaimana mestinya. Keadaan kegentingan yang memaksa yang dimaksud di sini berbeda dan tidak boleh dicampur adukan dengan pengertian keadaan bahaya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 12 UUD 1945. Pasal 12 tersebut menyatakan, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Kedua ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 tersebut sama-sama dari ketentuan asli UUD 1945, yang tidak mengalami perubahan dalam Perubahan Pertama sampai dengan Perubahan Keempat, artinya norma dasar yang terkandung di dalamnya tetap tidak mengalami perubahan (kursif penulis). Kusnardi dan Sarigih (1986;78) menyatakan bahwa pasal ini sebenarnya merupakan kekecualian dari prosedur pembuatan undang-undang yang biasa, karena keadaan yang genting dan yang memaksa. Dua unsur tersebut di atas itu merupakan syarat untuk berlaku kekecualian itu, artinya jika keadaan-keadaan itu telah genting namun belum memaksa, maka belum perlu kiranya untuk dipergunakan Pasal 22 itu. Menurut Mahmud MD dan Marbun (2000;30) bahwa dasar pemberian kewenangan ini adalah solus populi supreme lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Namun, untuk dapat mempersempit adanya penyalahgunaan terhadap pasal tersebut, Huda (2007;78) menyatakan bahwa hal ikhwal kegentingan yang memaksa ini hanya mengutamakan unsur: (i) kebutuhan hukum yang bersifat mendesak (proporsional legal necessity), sementara (ii) waktu yang tersedia sangat terbatas (limited time) dan tidak memungkinkan untuk ditetapkannya undang-undang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum itu. Senada dengan pendapat Huda, maka Basah (dalam Syofian dan Hidayat,2004;11) menyatakan bahwa kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang muncul secara tiba-tiba di mana hukum (peraturan perundang-undangan) tidak mengaturnya, serta dapat dipertangungjawabkan secara hukum dan moral. Dengan demikian, pertanggungjawabkan yang utama dalam penetapan Perpu tidaklah dapat diukur melalui hukum. Tidak lain karena memang merupakan salah satu daripada tugasnya, yang bahkan merupakan kewenangannya, yang mana semua tersebut dilakukan berdasarkan penilaiannya sendiri, untuk kemudian dituangkan ke dalam suatu kebijaksanaan, namun
I Gusti Ngurah Santika, SPd
228
haruslah tetap berdasarkan kepada kepatutan, yang tentunya dapat juga dipandang secara moral. Pendapat yang tidaklah jauh berbeda juga diberikan Sadjijono (2008;68) yang menyatakan bahwa wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri tersebut dalam rangka menjalankan kewajiban hukum dan kewajiban tugas, maka di dalam melakukan tindakan hukum wajib berpegang pada norma hukum maupun moral. Namun, Soekanto (1989;29) menyatakan di dalam peranannya itu, dia melaksanakan diskresi yang mempengaruhi hak-hak dari warga-warga masyarakat. Hukum memberikan patokan agar diskresi tersebut dibatasi, akan tetapi juga menghendaki kebebasan agar tercapai keadilan bagi para warga masyarakat. Sehingga hukum telah memberikan patokan bagi dilaksanakan diskresi, bahkan memang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai keadilan. Menurut Kusnardi dan Sarigih (2008;93) bahwa kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah, asalkan kebijaksanaan itu tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Inilah unsur-unsur demokrasi yang harus dijamin oleh undang-undang dan karena itu negara hukum adalah negara demokrasi di mana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh undang-undang. Berkaitan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka dalam pengertian kegentingan yang memaksa itu terkandung sifat darurat atau emergency yang memberikan alas kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu atau yang sering disebut undang-undang darurat menurut Konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950, atau emergency legislation menurut ketentuan konstitusi di berbagai negara lain. keadaan bahaya seperti yang dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 memang dapat menjadi salah satu sebab terpenuhinya persyaratan kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 itu. Akan tetapi, kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 itu tidak selalu bersumber dari keadaan bahaya menurut ketentuan Pasal 12. Pengertian bahaya itu dapat saja diartikan sebagai ancaman yang datang dari luar atau ancaman eksternal, tetapi keadaan genting dan memaksa dapat timbul sebagai akibat ancaman dari luar ataupun sebagai akibat tuntutan yang tak terelakan (Asshiddiqie,2006) Dari segi lain, keadaan bahaya yang datang dari luar itu dapat dilihat secara obyektif fakta-fakta yang ada, sehingga objektif atau tidaknya dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan kegentingan yang memaksa timbul dari penilaian subjektif Presiden belaka mengenai tuntutan mendesak dari dalam pemerintahannya untuk bertindak cepat dan tepat mengatasi keadaan yang genting. Pasal 22 kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden dalam bidang pembentukan undang-undang. Dengan demikian, ketentuan ini adalah sama halnya dengan penyerahan kekuasaan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
229
legislatif dari konstitusi kepada Presiden. Penyerahan atau pelimpahan kekuasaan, wewenang membuat undang-undang dari badan pembuat undang-undang kepada badanbadan administrasi negara, disebut delegasi perundang-undangan (Delegatie van wetgeving) (Mustafa,2001;51). Untuk itu, telah ditegaskan di dalam UUD 1945 bahwa terkait dengan pengawasan terhadap Perpu diserahkan sepenuhnya kepada DPR, yang nantinya akan melakukan pengujian (legislative reviw) terhadap Perpu tersebut, agar tidak melanggar ketentuan UUD 1945. Janganlah sampai terjadi seperti pada waktu zaman Orde Lama, banyak peraturan pemerintahan undang-undang yang pada dasarnya bertentangan dengan jiwa UUD 1945, yang notabene memberikan delegasi kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya, pada masa kepemerintahan Megawati Soekarno Puteri selama tiga setengah tahun gelombang demokratisasi berjalan terus sampai UUD 1945 yang dipandang sakral, juga direformasi dengan diamandemen sebanyak empat kali oleh MPR sehingga melahirkan sistem politik yang menginginkan Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat(Cangara,2009;11). Hal mana adanya ketentuan ini merupakan perubahan yang dapat dianggap cukup radikal, di mana diketahui sebelumnya berkenaan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak (lihat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen). Dengan kata lain, bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ketika itu dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara menyerahkan wewenang untuk memilihnya kepada wakil-wakil rakyat yang ada di MPR. Dengan demikian, tentu berkaitan terpilih atau tidaknya Presiden dan Wakil Presiden adalah kewenangan yang berada sepenuhnya di tangan MPR. Yang berarti kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden bukan berada di tangan rakyat berdaulat, yang sebenarnya telah ditentukan sebagai pemilik asli daripada kedaulatan tersebut. Ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen, yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Dengan adanya ketentuan ini, dapatlah diketahui dengan jelas bahwa UUD 1945 tersebut menghendaki berkaitan dengan tata cara untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden haruslah dipilih dan ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Namun, jika kita telusuri kembali dalam sejarahnya, terutama sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, kususnya terkait dengan calon yang akan menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden, mungkin bisalah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
230
dikatakan bahwa merupakah suatu tradisi, yang dalam kenyataan sejarahnya ternyata hanya ada satu calon tunggal untuk pemilihan jabatan Presiden yang maju untuk kemudian ditetapkan sebagai Presiden. Untuk mempertegas pernyataan tersebut, maka dapat diketahui dalam sejarah, khususnya pada saat adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dilakukan oleh PPKI, dimana pada waktu itu hanya terdapat satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk ditetapkan secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh PPKI yaitu Soekarno dan Hatta. Ternyata kemudian peristiwa ini berlanjut kembali, di era Orde Lama berkuasa, yaitu dengan dipilihnya Soekarno oleh MPRS sebagai Presiden, bahkan lebih lanjut penggangkatan tersebut dikukuhkan secara hukum, yaitu dengan Ketetapan MPRS No. III/MPR/1963, yang pada dasarnya ketentuan tersebut menyatakan, bahwa Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Kemudian tradisi calon tunggal pengsian jabatan Presiden dilanjutkan kembali pada masa Orde Baru, dengan terpilihnya Soeharto berkali-kali sebagai Presiden dan barulah berakhir, yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian untuk sekarang tidaklah demikian, apalagi setelah diamandemennya UUD 1945, khususnya tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ternyata tentukan untuk dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia dalam pemulu. Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, kemudian dengan tegas dicantumkan dalam ketentuan UUD 1945 setelah diamandemen, yang menyatakan bahwa untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah dipilih melalui pemilu. Dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 telah ditentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan adanya ketentuan ini, maka untuk sekarang, suara rakyatlah yang akan menentukan kemudian, siapakah yang nantinya terpilih untuk selanjutnya menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya akan memimpin rakyat melalui pemerintahannya selama lima tahun ke depannya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan benar-benar merupakan kehendak rakyat, yang dikarenakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan pilihan langsung rakyat sendiri. Lebih lanjut, terkait dengan terpilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, disertai dengan diharapan agar Presiden dan Wakil Presiden nantinya dapat menyelenggarakan kekuasaan dengan tenang tanpa bisa dijatuhkan sewaktu-waktu dalam masa jabatannya di tengah jalan oleh lembaga legislatif. Tidak lain dikarenakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan legitimasi yang tinggi untuk menduduki jabatannya, yaitu lewat dukungan yang diberikan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
231
oleh rakyat secara langsung dalam pemilu. Dengan demikian, suara rakyat secara langsung merupakan pemegang peranan yang utama dalam perpolitikan di Indonesia, utamanya untuk menentukan terpilih atau tidaknya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menduduki jabatan Presiden dan Presiden. Berarti, keterlibatan rakyat dalam rekruitmen elit politiknya bersifat langsung (Kleden,2004;16). Implikasi dari adanya pemilihan langsung terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tentunya akan berbeda pula dengan sebelumnya. Implikasi dari adanya calon Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian dipilih oleh MPR, maka mau tidak mau, Presiden dan Wakil Presiden haruslah mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya terhadap lembaga yang dahulu memilihnya, sebagai bentuk daripada akuntabilitas Presiden dan Wakil Presiden terpilih terhadap lembaga yang dulu memilihnya. Bahkan, terkait dengan kebenaran pernyataan ini, dapatlah dilihat kemudian dalam ketentuan Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, pada intinya penjelasan tersebut menyatakan bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Ia ialah mandataris dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak neben, akan tetapi untergeornet kepada Majelis. Untuk selengkapnya bunyi dari Penjelasan sebagaimana dimaksudkan di atas, terkait dengan adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, yang mana membawa akibat pula terhadap kedudukan serta pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden terpilih kepada MPR, yaitu. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah mandataris dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak neben, akan tetapi untergeordnet kepada Majelis (kursif penulis). Dalam sejarahnya ternyata sudah ada dua Presiden yang sebelumnya pernah diminta pertanggung jawabannya, khususnya terhadap tugas-tugasnya yang dulu diembankan oleh MPR, pertanggungjawaban tersebut dengan melalui Sidang Istimewanya, Presiden yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Soekarno yang merupakan Presiden Pertama dan Abdurahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur merupakan Presiden Keempat.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
232
Untuk lebih lanjutnya, terkait dengan adanya pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden, nantinya akan dibahas kembali di bawah. Terkait dengan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan, berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah kemudian dikatakan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, merupakan satu-kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalah satu kesatuan lembaga kepresidenan. Namun demikian, keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. Karena itu, meskipun di satu segi keduanya, merupakan dua organ negara yang berbeda satu sama lain, namun sebagai dua organ yang tak terpisahkan, tetapi dapat dan harus dibedakan satu sama lain. Dengan begitu, berakibat pula terhadap adanya suatu pertanggungjawaban Presiden Wakil Presiden secara politik yang merupakan satu kesatuan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan kemudian untuk pertanggungjawabannya secara hukum, merupakan terpisah antara Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Selanjutnya, tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dinyatakan dalam UUD 1945, yaitu ketentuan Pasal 6A yang di dalamnya terdiri dari 5 ayat. Pemilihan Presiden langsung adalah buah dari perdebatan yang muncul pada paruh pertama tahun 2000. Pada masa itu, pengalaman pahit yang terjadi pada proses pengisian jabatan Presiden selama Orde Baru dan proses pemilihan Presiden tahun 1999, mendorong untuk dilakukan pemilihan Presiden langsung, karena beberapa alasan (raison detre) yang sangat mendasar. 1. Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Kemauan orang-orang yang memilih (volonte generale) akan menjadi pegangan bagi Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya. 2. Pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Intrik politik akan dengan mudah terjadi dalam sistem multipartai. Apalagi kalau pemilihan umum tidak menghasilkan partai pemenang mayoritas, maka tawar-tawar politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan. 3. Pemilihan Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. Kecenderungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara aspirasi rakyat dengan wakilnya. Ini semakin diperparah oleh dominannya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
233
pengaruh partai politik yang telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik (political party representation). 4. Pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat. Sebelum perubahan UUD 1945, misalnya, yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR menjadi sumber kekuasaan dalam negara karena adanya ketentuan bahwa lembaga ini adalah pemegang kedaulatan rakyat. Kekuasaan inilah yang dibagi-bagikan secara vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi negara lain termasuk kepada Presiden. Akibatnya, kelangsungan kedudukan Presiden sangat tergantung kepada MPR (Isra,2009;108-109). Tentunya terkait dengan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden setelah amandemen UUD 1945, dengan sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945 akan berbeda. Kedudukan sebagaimana dimaksud penulis adalah berkaitan dengan derajat legitimasinya, serta kedudukannya terhadap lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian, pendapat yang ada kaitannya dengan derajat legitimasi yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden, karena dipilih oleh rakyat melalui pemilu dinyatakan oleh Muhsin (2009;120) yang pada pada garis besarnya menyatakan bahwa melalui pemilu, legitimasi pemerintah dikukuhkan karena mereka adalah hasil pilihan warga negara yang memiliki kedaulatan. Sehingga dengan demikian, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidaklah kemudian dapat dijatuhkan secara sepihak oleh lembaga politik tanpa adanya kehendak rakyat sendiri. Pendapat bernada sama juga dinyatakan oleh Marzuki (2010;16) bahwa kedudukan Presiden/Wakil Presiden cukup kuat, tidak dapat dijatuhkan secara politis dalam masa jabatannya, artinya Presiden/Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan akibat putusan kebijakan (doelmatigheid beslissing) yang ditetapkan atau dijalankan Presiden/Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun, secara teoritik sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan konsekuensi dari penggunaan sistem presidensil (Latif,2009;27). Dengan demikian, dapatlah diperoleh suatu kesimpulan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD 1945, merupakan suatu konsekuensi logis untuk kemudian diadakannya pemilihan umum, yang khususnya dilaksanakan untuk pemilihan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Karena itu, tentunya Presiden dan Wakil Presiden telah mendapatkan legitimasi tinggi dari rakyat, tidaklah dapat dijatuhkan dari jabatannya secara sepihak oleh lembaga politik, kecuali hanya dengan pranata impeachment, yang telah ditentukan terbatas mengenai alasan maupun tata caranya dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
234
UUD 1945. Di mana prosedur tersebut didahului dengan adanya dugaan dari DPR yang menyatakan tegas melalui pendapatnya, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran lainnya dengan syarat yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kemudian pendapat tersebut akan diuji kembali lewat forum previlegiatum di MK, yang lewat putusannya dapat menyatakan apakah benar Presiden dan/atau Wakil Presiden itu terbukti telah melanggar hukum, yang kemudian putusan MK merupakan putusan final, apabila dalam keputusannya menyatakan bahwa pendapat DPR tidak terbukti. Namun, merupakan jalan bagi DPR untuk meneruskan kembali ke MPR, apabila putusan MK membenarkan pendapat DPR. Dengan demikian, masih saja terlihat nuansa politik yang selanjutnya mengiringi proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, dikarenakan kewenangan terakhir untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah terletak di tangan MPR. Itulah keuntungan daripada di adakannya pemilihan secara langsung terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yang kedudukannya tidaklah bergantung sepenuhnya kepada kekuatan politik yang mendukungnya, terutama yang ada di parlemen. Dengan pemilihan secara langsung, Presiden tidak mutlak memerlukan poitical support dari parlemen, Presiden mempunyai jabatan yang sudah pasti (fix term), sehingga tidak dapat digantikan karena hilang atau berkurang dukungan parlemen (Nasution,2009;72). Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan Ristawati (2009;14) bahwa mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam jangka waktu yang pasti memberikan konsekuensi terhadap kedudukan lembaga eksekutif tersebut untuk tidak tergantung pada dinamika lembaga-lembaga negara yang lain. Dengan kata lain, jika eksekutif dipilih secara langsung maka ia memiliki basis pemilih sendiri sehingga tidak tergantung pada badan legislatif (Sidqi,2008;34). Dalam arti kedudukan Presiden adalah sebanding dengan DPR, dalam menjalankan pemerintahan menurut UUD 1945, tentu dikarenakan kedua lembaga negara tersebut sama-sama adalah pilihan rakyat. Dan dapat dipastikan untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidaklah mungkin mudah diraih, dikarenakan bahwa dalam UUD 1945 telah dipersyaratkan untuk mendapatkan sebagian besar daripada suara rakyat, yang tentunya akan berbeda dengan pemilihan anggota legislatif. Sehingga dapat dipastikan bahwa kandidat yang terpilih secara demokratis mendapat dukungan dari bagian besar dari masyarakat pemilih (Legowo,2005;2). Maka sesuai dengan teori demokrasi, maka pada prinsipnya bahwa setiap adanya pengisian jabatan pemerintahan, haruslah berdasarkan pada kehendak rakyat yang merupakan locus kedaulatan. Namun tidak berarti bahwa pemimpin yang terpilih secara
I Gusti Ngurah Santika, SPd
235
demokratis secara otomatis akan terjamin keberpihakannya kepada aspirasi rakyat yang telah memilihnya melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Walaupun seperti itu, namun tetap saja negara yang mengaku pemerintahannya demokratis adalah sebuah negara dengan peletakan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga pemerintahan yang berjalan memang adalah berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dipandang lebih tepat apabila ingin memberikan makna optimal terhadap kedaulatan rakyat sekaligus juga lebih demokratis karena rakyat langsung memberikan suaranya untuk memilih pemimpin negara/pemerintahan yang dikehendakinya (Asshiddiqie,2009;299). Lebih lanjut terkait dengan adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat, ternyata ada ketentuan baru terkait dengan siapa saja yang kemudian dapat menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Bila kita melihat kembali, maka menurut ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 tepatnya Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (kursif penulis). Ketentuan konstitusional tersebut, akan berbeda sekali dengan ketentuan sebelumnya, yang kemudian dapat diketahui kembali dalam ketentuan dari Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum diamandemen, yang dengan tegas menyatakan bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli(kursif penulis). Dalam perjalanan sejarahnya, dalam kenyataannya dengan adanya ketentuan dari Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, telah menimbulkan makna yang dapat kemudian dikatakan ambigu/multitafsir, apakah yang selanjutnya dimaksudkan dengan orang Indonesia asli? apakah orang yang dilahirkan di Indonesia (ius soli) atau yang orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia (ius sanguinis). Kemudian dengan adanya ketentuan Pasal 6 UUD 1945 setelah diamandemen, maka kita dapatlah mengetahui lebih jelas apa yang sesungguhnya diinginkan oleh ketentuan Pasal 6 UUD 1945 setelah diamandemen tersebut di atas. Dalam ketentuan Pasal 6 UUD 1945, terdapat kata Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Dengan kata lain, dapat diartikan hanya untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden saja, orang tersebut sudah haruslah sebelumnya menganut kewarganegaraan Indonesia, khususnya sejak kelahirannya. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang telah ditentukan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
236
secara konstitusional dalam UUD 1945. Terlebih dahulu perlulah untuk diketahui berkaitan dengan adanya asas kewarganegaraan yang telah dianut suatu negara, di mana pada umumnya dikenal adanya asas kewarganegaraan yang kemudian kembali dibagi menjadi dua, yaitu azas kewarganegaraan suatu negara yang mendasarkan keturunan (ius sanguinis), yaitu menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, dengan demikian tidaklah bergantung pada tempat dimana dilahirkannya orang tersebut. Lebih jelas lagi bahwa anak tersebut merupakan anak yang sebelumnya dilahirkan oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dimanapun juga (misalnya kalau orang tuanya warga negara Indonesia, maka secara otomatis terhadap anak yang dilahirkannya kemudian juga adalah berkewarganegaraan Indonesia tanpa menentukan dimana anak tersebut dilahirkan, asalkan orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia). Selain adanya azas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan, kemudian dikenal pula kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (ius soli), yaitu asas yang pada dasarnya menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ditempat di mana orang tersebut dilahirkan (misalnya kalau anak yang ahir di Amerika Serikat, maka akan secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Amerika Serikat. Dalam pada itu, tentunya jika anak tersebut lahir di luar negara tersebut, maka ikatan kewarnegaraannya akan terputus dengan orang tuanya yang sebelumnya pada dasarnya menganut kewarganegaraan Amerika Serikat). Maka berdasarkan paparan tersebut di atas, yang kemudian dimaksudkan berdasarkan sejak kelahirannya menurut UUD 1945, adalah ketentuan yang berdasarkan keturunan (ius sanguinis). Hal mana dikarenakan bahwa hanya anak yang kemudian dilahirkan oleh orang tua yang sebelumnya sudah berkewarganegaraan Indonesia lah dapat secara langsung mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sehingga, dapatlah kelak dikemudian hari, orang tersebut dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, karena telah langsung mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jika pernyataan tersebut tepat, maka tentunya berakibat pula bahwa secara otomatis telah menutup peluang, jika pada suatu saat orang tersebut dilahirkan ternyata tidaklah memiliki berkewarganegaraan Indonesia, dengan demikian dia tidak berhak untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut sangatlah tegas, dikarenakan dapat saja orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia sejak dilahirkan/orang asing, kemudian berniat untuk menjadi warga negara Indonesia, yaitu dengan cara naturalisasi misalnya. Kemudian hal tersebut dipertegas kembali dengan kata Calon Presiden dan Wakil Presiden juga tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Menurut sejarahnya, adanya ketentuan ini dikarenakan dahulunya Presiden Habibie, dikatakan pernah menerima pula kewarganegaraan lainnya, yaitu kewarganegaraan Jerman. Adanya ketentuan ini
I Gusti Ngurah Santika, SPd
237
merupakan suatu komitmen bahwa Presiden Indonesia tentunya harus memiliki sifat-sifat nasionalisme, yang mungkin menurut ketentuan konstitusi sifat tersebut hanya akan dimiliki jika kewarganegaraan Indonesia yang mungkin diperolehnya sejak dilahirkan. Diharapkan pula, bahwa orang yang nantinya menjadi Presiden dan Wakil Presiden, benarbenar orang memiliki integritas, kapabilitas, terutama rasa cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negaranya. Tentunya persyaratan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak kalah pentingnya adalah orang tersebut tidaklah pernah mengkhianati negara. Yang dimaksudkan dengan tindakan tidak pernah mengkhianati negara adalah tidak pernah melakukan gerakan-gerakan yang memiliki potensi untuk membahayakan keutuhan dan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian ada persyaratan yang menyatakan bahwa Jabatan Presiden dan Wakil merupakan suatu tugas yang berat, sehingga dicantumkan pula kata mampu secara rohani dan jasmani menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Adanya ketentuan ini tidak terlepas daripada sejarah kepemimpinan bangsa Indonesia, di mana dulunya pernah memiliki Presiden yang dapatlah kemudian digolongkan tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugasnya sebagai Presiden. Selain adanya persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden seperti tersebut di atas, kemudian disebutkan pula dalam ketentuan lainnya, yaitu Pasal 6 UUD 1945, yang menunjukan bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, telah memberikan kesempatan dan bahkan memonopoli berupa keterlibatan partai politik atau gabungan partai politiklah, untuk dapat mengajukan usul pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilu. Selengkapnya bunyi dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum(kursif penulis). Ketentuan ini jelas berbeda dengan sebelumnya, dimana dalam UUD 1945 sebelum diamandemen tidaklah menyebut-nyebut adanya partai politik. Namun, untuk sekarang ini bahkan dengan jelas telah disebutkan dalam konstitusi bahwa berkaitan dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, haruslah dari partai politik atau gabungan partai politik. Tentunya jika suatu partai politik ternyata mampu secara sendirian untuk memenuhi persyaratan guna mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka konstitusi telah memberikan kesempatan berpikir kepada partai politik untuk tidaklah perlu mempertimbangkan membantuk koalisi dengan partai politik lainnya, untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, kekuasaan sepenuhnya berada pada partai politik tersebutlah, untuk selanjutnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
238
mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan untuk kemudian mengikuti pemilu. Tetapi tentunya, konstitusi tidak pula melarang, misalnya partai politik yang sudah memenuhi syarat untuk selanjutnya mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian bergabung untuk membentuk koalisi dengan partai politik lainnya, sehingga kekuatan politik lebih besar untuk mendukung dan menyukseskan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden agar kemudian dapat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, jika sudah berkoalisi tentunya berkaitan dengan distribusi kekuasaan perlulah kemudian menjadi pertimbangan utama, agar integrasi dan solidaritas dari koalisi tersebut menjadi kokoh. Sebaliknya, jika seandainya suatu partai politik tidaklah memenuhi syarat untuk kemudian mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dapatlah memanfaatkan kata gabungan partai politik dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Setidaknya dengan adanya ketentuan tersebut secara langsung telah mengijinkan/memberikan jalan bagi partai-partai politik, khususnya partai politik yang tidak memenuhi syarat, kemudian membentuk koalisi untuk selanjutnya bersama-sama mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dengan demikian dapatlah memenuhi syarat yang ditentukan kemudian dalam undang-undang, terkait persyaratan tersebut di atas. Dalam hal ini, jika suatu partai politik tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga merupakan suatu pilihan yang tidak dapat ditentukan lagi oleh partai politik tersebut, untuk kemudian selanjutnya haruslah mengadakan suatu koalisi, sehingga terpenuhilah persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang, yang kemudian mengaturnya persyaratan seperti apa yang dimaksudkan oleh UUD 1945. Bahkan dengan adanya ketentuan ini, banyak pendapat yang mengatakan bahwa secara tidak langsung bangsa Indonesia telah ditakdirkan untuk menganut sistem kepartaian dengan jumlah partai lebih dari 1 partai (multi partai). Karena ketentuan tersebut di dalamnya terdapat kata gabungan, sehingga partai politik ketika pemilu diharapkan jumlah nantinya terdapat lebih dari satu partai politik. Dengan demikian, UUD 1945 telah menggariskan secara garis besarnya bahwa sistem kepartaian yang harus dianut oleh Indonesia sebagai negara demokrasi adalah sistem multipartai, setidaknya sistem kepartaian yang dianut sekarang bukanlah satu partai. Berkaitan dengan sistem kepartaian yang dikenal, perlulah diketahui pendapat dari Maurice Duverger yang membaginya menjadi tiga katagori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi-partai (Budiardjo,2008;415). Dalam sejarahnya sistem multi partai pernah juga diterapkan di Indonesia, khususnya pada saat belangsung sistem demokrasi dengan liberal sebagai labelnya, yaitu pada era tahun 1950 yang ketika itu sistem pemerintahannya adalah parlementer, dengan asas mengutamakan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
239
tanggungjawab pemerintahan oleh menteri kepada parlemen, yang akhirnya berujung pada ketidakstabilan politik pemerintahan. Kemudian pada era Orde lama, partai politik tidaklah mendapatkan tempat yang sepantasnya, bahkan peraturan yang bertugas mengatur kebebasan dalam mendirikan partai politik dicabut dan diganti dengan peraturan yang bertujuan untuk membatasi berdirinya partai politik, sehingga partai politik yang diakui pada waktu itu hanya 10. Namun, partai politik tersebut tidaklah dapat berkembang, karena demokrasi sebagai tangganya tidak pernah dilaksanakan, bahkan pemilihan umum sebagai anak demokrasi, dalam kenyataannya tak pernah diselenggarakan pada periode ini, sehingga partai politik menjadi tidak berkembang, seperti di negara-negara lainnya yang pada dasarnya menganut demokrasi. Kemudian pada saat Soeharto dengan Orde Baru sebagai julukannya, melengkapi sistem kepartaian yang dianut Indonesia, yaitu dengan sistem multi partai terbatas. Hal mana dikarenakan pada waktu itu hanya terdapat tiga partai politik yang diperbolehkan berkompetisi, untuk mengikuti pemilihan umum dan tidaklah diperbolehkan mendirikan partai politik, selain ketiga organiasasi politik tersebut, bahkan salah satu kontestan, yaitu Golkar, tidaklah kemudian dianggap sebagai partai politik. Golkar mendapatkan perlakuan yang sangat spesial berupa dukungan dari pemerintah, yang ternyata berbeda dengan kedua rivalnya terutama dalam merebut suara rakyat, sehingga hanya Golkar lah yang selanjutnya dapat terus menerus menang dalam pemilu selama ini. Lebih lanjut terkait dengan adanya pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, berupa partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang sebelumnya telah memenuhi syarat, untuk selanjutnya mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, haruslah diajukan kemudian sebelum adanya pemilihan umum. Ketentuan ini merupakan penegasan terhadap batas waktu, untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat dipastikan hanya partai politiklah merupakan satu-satunya wahana bagi sesorang, untuk mengajukan dirinya sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga untuk itu seseorang, yang ingin menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah memanfaatkan partai politik, guna mendapatkan suara rakyat dalam bersaing untuk selanjutnya merebut kekuasaan pemerintahan. Ketentuan tersebut juga menyiratkan agar nantinya partai politik merupakan penghubung antara rakyat dan pemerintahan, sehingga diharapkan partai politik benar-benar merapat dengan rakyat supaya benar-benar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, tanpa itu partai politik
I Gusti Ngurah Santika, SPd
240
hanyalah sebagai instrumen yang bisa saj menjadi cambuk bagi demokrasi itu sendiri. Partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi karena mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintahan negara (the state) dengan warga negaranya (the citizen) (Nazaruddin,2009;59). Untuk Indonesia pasca reformasi UUD 1945, telah menempatkan partai politik sebagai salah satu aktor yang memiliki kedudukan penting, bahkan menentukan dalam kehidupan demokrasi. Dengan adanya kata gabungan maka konsekuensinya bahwa Indonesia menganut sistem presidensial dengan sistem kepartaian yang multipartai. Ketentuan ini sangatlah mirip pada waktu setelah kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Pada tanggal 3 November 1945, Pemerintah RI telah mengeluarkan maklumat yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan (Poerwantana,1994;26). Dengan demikian, menurut penulis kedua ketentuan tersebut di atas, adalah sama-sama memiliki arti yang sangat penting secara konstitusional, bahkan dapatlah kemudian disetarakan kedudukannya sebagai hukum yang bersifat mendasar, karena memang sangatlah diperlukan terutama oleh negara yang mengaku pemerintahannya adalah demokratis, serta berusaha untuk meletakan kehendak rakyat sebagai dasar daripada tindakan pemerintahan. Memang banyak kelebihan yang mungkin didapatkan dengan dianutnya sistem kepartaian yang multipartai. Apalagi sistem demokrasi modern seperti sekarang ini yang pada prinsipnya mengutamakan perwakilan sebagai konsep yang paling utama. Sistem multipartai sebagai sistem keterwakilan tiap kelompok sebagai maksud untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah merupakan representasi aspirasi masyarakat yang harus diakomodir (Aminah,2009;73). Dalam ketentuan ayat (3) dari Pasal 6A UUD 1945 telah diatur pula mengenai jumlah perolehan suara sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sebagai kontestan dalam mengikuti pemilihan umum, untuk dapat menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden. Selengkapnya ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 berbunyi bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (kursif penulis). Menurut pengertian penulis, dalam ketentuan pasal ini terdapat dua syarat, untuk dapat dinyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kemudian terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pertama, bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan suara pemilih lebih dari lima puluh persen dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
241
pemilihan umum. Dengan jumlah suara yang diraih oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari lima puluh persen, maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tersebut, tentunya memiliki tingkat legitimasi yang lebih kuat, karena mendapatkan suara yang besar dari rakyat, yaitu dengan jumlah suara mayoritas. Kedua, setidaknya jumlah suara lebih daripada lima puluh persen yang didapatkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut haruslah tersebar secara merata di setiap provinsi, yang dalam hal ini telah dipersyaratkan, yaitu paling tidak pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen tersebut yang kemudian disusul dengan sedikitnya dukungan kemenangan suara diperoleh adalah sebanyak dua puluh persen, yang selanjutnya dipersyaratkan kembali bahwa dukungan tersebut haruslah tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa adanya ketentuan agar jumlah suara 50 persen yang sebelumnya diraih oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Menurut penulis adanya ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan bagi kemenangan suara yang harus diraih oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian kemenangan suara tersebut haruslah tersebar kemudian, dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dimaksudkan agar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya terpilih, dikarenakan jumlah suara yang dipersyaratkan tersebut telah terpenuhi hanya disatu daerah saja, hal mana tersebut bisa saja terjadi, dikarenakan adanya ketidakmerataan persebaran penduduk di Indonesia. Jadi, akan berbeda jumlah penduduk antara di Kalimantan yang daerahnya berpenduduk jarang dengan penduduk padat yang ada di daerah lain tersebut, seperti daerah Jawa. Sehingga bisa saja, tanpa adanya ketentuan ini, seorang calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya popular di daerah Jawa misalkan, dikarenakan dengan jumlah penduduk yang demikian besar, bahkan menurut konstitusi sudah melebihi dari setengah jumlah suara yang persyaratkan, untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kemungkinan besar pemilu Presiden dan Wakil Presiden ternyata hanya dapat diputuskan oleh penduduk Jawa. Dengan demikian, bisa saja hanya dengan dukungan suara di Jawa saja, memungkinkan untuk dapat kemudian menentukan terpilih tidaknya pasangan calon Presiden dan Wakil Indonesia. Hal ini pada gilirannya ke depan akan menjadi penyebab timbulnya perasaan primordialisme antara daerah-daerah lainnya di Indonesia, yang pada gilirannya kemudian akan menyebabkan munculnya benih-benih disintergrasi bangsa. Dikarenakan sudah dapat dipastikan bahwa yang akan menjadi pemimpin, khususnya untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah hanya untuk orang-orang dari suku tertentu. Tidak lain dari pengalaman masa lalu kita telah belajar, di mana sering terjadi suatu tindakan yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
242
mencoba untuk menentang berbagai keputusan yang datang dari pusat, dikarenakan merasa adanya ketidakadilan terutama dalam rangka pengisian jabatan-jabatan publik, yang ternyata hanya didominasi dari suku tertentu saja. Menurut Mahmud (2010;140) bahwa ketentuan yang demikian sekaligus juga menyiratkan adanya tuntutan akan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dua putaran, manakala dalam sekali putaran tidak pasangan calon yang memperoleh dukungan lebih dari 50 persen secara nasional dan 20 persen di sekurangnya separuh provinsi yang ada di Indonesia. Pernyataan di atas memang benar, adanya ketentuan tersebut adalah untuk memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat secara merata, dan tentunya persyaratan ini sangat sulit untuk dapat diperoleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dengan satu kali putaran pemilihan umum. Oleh karenanya, dalam ketentuan ayat (4) dari Pasal 6A UUD 1945 ditentukan bahwa Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara rakyat terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden(kursif penulis). Pasal ini merupakan jalan keluar yang diberikan oleh UUD 1945, bilamana persyaratan suara yang ditentukan untuk diperoleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak tercapai, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (3) dari Pasal 6A UUD 1945. Bisa saja hal tersebut terjadi, dikarenakan partai politik maupun gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua. Sehingga jumlah suara yang didapatkan oleh kontestan pemilu pertama Presiden dan Wakil Presiden ternyata bisa saja, tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi. Dengan demikian, maka selanjutnya kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam pemilihan umum pertama mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua, kemudian akan kembali mengikuti pemilihan umum selanjutnya, yaitu pada putaran kedua, sampai kemudian terpenuhinya jumlah suara rakyat yang telah ditentukan dalam konstitusi, untuk dapat dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Jadi setelah adanya putaran kedua pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, nampaknya UUD 1945 tidak lagi mensyaratkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak haruslah merata dukungannya di setengah jumlah provinsi di seluruh Indonesia sebagai mana bunyi ayat sebelumnya. Namun, penulis berpendapat hal tersebut memang tidaklah diperlu untuk dicantumkan kembali, dikarenakan bahwa hanya terdiri dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka sudah dapat dipastikan kemenangan suara yang didapatkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tentunya sudah merata di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui
I Gusti Ngurah Santika, SPd
243
lebih lanjut, terkait dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, UUD 1945 memberikan perintah pengaturannya kembali dalam bentuk undang-undang, kemudian dapatlah diketahui dalam ketentuan dari Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Sepengetahuan penulis berkaitan dengan pengaturan tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di dalam undang-undang, yaitu dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2003 dan untuk yang terakhir telah ada ketentuan UU No. 42 Tahun 2008. Selain adanya ketentuan Pasal 6A UUD 1945 yang mengatur secara garis besar tentang syarat-syarat pemilihan umum bagi Presiden dan Wakil Presiden, yang dengan demikian telah membuktikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentunya memiliki derajat legitimasi yang sangat tinggi, karena merupakan pilihan langsung dari rakyat. Oleh karena itu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak mungkin dapat dijatuhkan dari jabatan sewaktu-waktu di tengah jalan, terutama oleh DPR dikarenakan alasan-alasan yang hanya bersifat politis. Bahkan, dengan tegas pula dinyatakan dalam UUD 1945, bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidaklah mungkin untuk dijatuhkan selama belum berakhir masa jabatannya, yaitu dalam jangka waktu lima tahun. Namun, juga telah ditentukan dalam UUD 1945, bahwa seseorang yang memegang kekuasaan tersebut haruslah pula diadakan pembatasan. Pembatasan terutama ditujukan terhadap periode jabatan Presiden yang dalam UUD 1945 sudah ditentukan, yaitu hanya dapat diduduki selama dua kali masa jabatan oleh orang yang sama, setelah itu ia tidaklah dapat lagi untuk diperkenankan menduduki jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan(kursif penulis). Ketentuan ini merupakan buah hasil dari amandemen pertama UUD 1945, dengan tujuan utamanya adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden, khususnya terkait dengan berapa periode seseorang boleh menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan dari Pasal 7 UUD 1945, oleh MPR ternyata setelah jatuhnya Presiden Soeharto telah ditetapkan pula dengan adanya Tap MPR No. VIII/MPR/1998, yang pada intinya telah membatasi seseorang untuk menjadi Presiden dengan memegang jabatan tersebut, yaitu hanya untuk dua periode saja. Sebelum adanya amandemen terhadap ketentuan Pasal 7 UUD 1945, pasal tersebut berbunyi bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali (kursif
I Gusti Ngurah Santika, SPd
244
penulis). Dalam sejarahnya ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sebelum diamandemen, telah menimbulkan penafsiran yang bersifat ganda atau multitafsir, dikarenakan dalam pasal tersebut terdapat kata dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Di mana pada waktu itu, ada sebagian pendapat para ahli yang menafsirkannya dengan menyatakan bahwa jabatan Presiden dapatlah terus dijabat selama-lamanya oleh orang yang sama. Dikarenakan menurut mereka bahwa dengan tidak adanya penegasan tentang pembatasan periode jabatan Presiden oleh UUD 1945 yang boleh diduduki seseorang, maka tidaklah perlu untuk dipermasalahkan kemudian, asalkan saja bahwa setiap lima tahun sesudah itu, yaitu setelah berakhir masa orang yang memegang jabatan Presiden tersebut, kemudian ternyata orang yang sebelumnya menjadi Presiden, dikarenakan memang telah berakhir jabatannya tersebut, kemudian dalam kenyataannya ia dikehendaki lagi oleh rakyat, untuk dipilih kembali menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu melalui wakilnya di MPR, maka tentunya ia akan dapat terus menjabat sebagai Presiden. Dengan adanya penafsiran seperti ini, yang sebelumnya dilakukan oleh pendukung-pendukungnya dan Soeharto sendiri, sehingga kemudian dapatlah ia terpilih kembali untuk selanjutnya menjabat menjadi Presiden berkali-kali, yang mana juga dikarenakan mendapatkan dukungan suara dari MPR, sehingga dapat terus menurut memegang kekuasaan pemerintahan selama 32 tahun sebagai Presiden Indonesia. Dengan demikian, Soeharto telah melihat peluang untuk dapat melakukan suatu tindakan berupa penyimpangan, yang kadang-kadang terlihat seperti konstitusional, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada konstitusi, khususnya tentang periode masa jabatan Presiden, di mana pada waktu itu memang tidak ditegaskan pembatasannya dalam UUD 1945. Namun, tentunya akan berbeda dengan yang terjadi pada waktu Soekarno ditetapkan oleh MPR sebagai Presiden seumur hidup, yaitu dengan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963. Karena tentunya memiliki makna yang berbeda pula antara UUD 1945, khususnya Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan, yang pada dasarnya menghendaki bahwa Presiden dan Wakil Presiden tersebut haruslah tetap dipilih setiap lima tahun oleh MPR dengan suara terbanyak, kemudian setelah berakhir masa jabatan tersebut, dikarenakan sudah menjabat selama lima tahun, maka kemudian harus dipilih kembali untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun dan begitu seterusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketetapan MPR tersebut adalah suatu ketentuan yang sifatnya sangat nyata bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, yang khususnya mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu selama lima tahun. Sedangkan, tafsiran lainnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sebelum diamandemen, menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanyalah boleh memegang jabatan selama lima tahun dan setelah itu dapat kemudian dipilih kembali untuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
245
jabatan yang sama hanya untuk kali lagi dalam masa jabatannya. Dengan demikian, tafsiran yang kedua ini bermaksud untuk membatasi sesorang yang berkehendak untuk memegang jabatan Presiden, yaitu maksimal selama dua periode dan setelah itu, dia tidaklah dapat kemudian dipilih kembali menjadi Presiden. Penulis sangatlah memahami maksud, dari pendukung menurut tafsiran yang kedua, yaitu dengan adanya suatu pembatasan terhadap periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dipegang oleh seseorang, maka tentunya dapatlah kemudian dihindari hal-hal yang mungkin akan berdampak negatif. Terutama bagi seseorang yang secara kebetulan memegang jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditentukan oleh UUD 1945, karena disebabkan oleh begitu besar kekuasaannya, sehingga akan memberikan peluang bahkan potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan, yang kemudian ujung-ujungnya akan semakin menyengsarakan rakyat. Pernyataan tersebut sudah terbukti dan dapat dikomfirmasi kembali dengan fakta-fakta sejarah yang sebelumnya dialami pada masa lalu, di mana Presiden Soekarno yang kemudian ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS No. III/MPR/1963. kemudian berlanjut kembali dengan terpilihnya Presiden Soeharto berkali-kali oleh MPR, telah menyebabkan siklus kekuasaan hanya berputar-putar sekitar penguasa saja, kemudian kekuasaan semakin mengeras bahkan ide perubahan pun tak bisa menyentuhnya. Oleh karena ide itulah yang kemudian menjadi dasar, dalam rangka melakukan perubahan terhadap UUD 1945, khususnya berkaitan dengan periode masa jabatan Presiden yang dapat dipegang oleh seseorang selama hidupnya. Maka untuk sekarang ini dengan adanya amandemen terhadap ketentuan Pasal 7 UUD 1945 menyebabkan seseorang hanya boleh menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama dua Periode, dikarenakan sesudah itu dia tidaklah dapat untuk dipilih kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun, dengan adanya masa jabatan Presiden yang tetap, yaitu selama lima tahun, maka dapatlah kemudian diartikan bahwa Presiden tidaklah kemudian dapat dijatuhkan sewaktu-waktu di tengah jalan oleh lembaga negara lainnya, terutama oleh lembaga legislatif (DPR) dikarenakan adanya alasan-alasan yang bersifat politik. Namun, dalam UUD 1945 ternyata telah membuka pula kesempatan, untuk meng- impeachment Presiden dan Wakil Presiden, jika memang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dan memenuhi syarat untuk di impeachment sebagaimana telah ditentukan dengan jelas alasananya di dalam UUD 1945. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial adalah kepala pemerintahan sekaligus juga sebagai kepala negara yang tidak mungkin dapat dijatuhkan dari jabatannya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
246
oleh lembaga negara lain terutama lembaga politik, dengan melakukan penilaian terhadap kebijaksanaannya, seperti yang terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. Adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam UUD 1945, merupakan suatu ciri bahwa negara tersebut adalah suatu negara hukum, yang mana setiap perbuatan ataupun tindakan dari pejabat, namun memiliki sifat yang melanggar hukum, haruslah selalu dapat dimintai pertanggungjawabannya kembali secara hukum pula. Termasuk tindakan Presiden, yang mungkin bisa saja, suatu hari melakukan perbuatan yang dapat dikatagorikan sifatnya bertentangan dengan hukum, terutama sebagaimana dimaksudkan UUD 1945. Dalam UUD 1945, telah ditentukan dengan baik terutama ketentuan Pasal 7A dan 7B tentang tata cara pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya, jika dalam kenyataannya melanggar larangan berupa ketentuanketentuan yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 tersebut. Dalam Pasal 7B UUD 1945 dinyatakan dengan jelas, bahwa MPR memiliki wewenang terutama dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, jika memang terbukti telah melanggar hukum dan melanggar larangan lainnya, seperti dipersyaratkan di bawah ini, bahwa. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaraan hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Kemudian selanjutnya merupakan mekanisme dalam melakukan impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, yang kemudian ditentukan secara jelas dalam ketentuan Pasal 7B UUD 1945, yang bunyinya sebagai berikut. 1. Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
247
2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaraan hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Pemusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (kursif penulis).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
248
Dengan adanya ketentuan ini, maka dapatlah kemudian dikatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menjabat tidaklah mungkin dapat dijatuhkan terutama dalam masa jabatannya, oleh dikarenakan kebijakannya tidak disepaham dengan lembaga politik, di mana biasanya hanya bisa terjadi di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Tidak lain dikarenakan terkait dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia adalah sesuai dengan sistem pemerintahan yang kemudian dianutnya, yaitu presidensial. Ketentuan ini tentunya akan berbeda sekali dengan sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, yang mengatur bagaimana tata cara Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertanggungjawabkan atas segala tindakannya kepada MPR yang pada waktu itu merupakan lembaga negara tertinggi. Di mana ketika itu Presiden sendiri merupakan mandataris dari MPR, sehingga kedudukannya berada di bawah posisi MPR. Intinya dicantumkan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, bahwa MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang sepenuh melaksanakan kedaulatan rakyat. Sedangkan Presiden memiliki tugas untuk menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang sebelumnya telah ditetapkan oleh MPR. Adanya ketentuan tersebut tidak lain disebabkan bahwa Presiden diangkat oleh MPR, yang berarti dia harus tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR. Presiden adalah mandataris MPR dan tentunya wajib untuk menjalankan putusan-putusan MPR. Presiden tidaklah boleh neben, akan tetapi untergeodrnet kepada MPR. Dengan adanya pertanggungjawaban tindakan Presiden terhadap MPR, setidaknya telah menimbulkan dua penafsiran yang berlawanan antara satu penafsiran dengan penafsiran yang lainnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut pada waktu itu adalah presidensial semu (quasi presidensial). Kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut pada waktu itu, adalah sistem pemerintahan presidensial murni. Menurut pendukung dari pendapat pertama, bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah quasi presidensial, dikarenakan adanya suatu pertanggungjawaban daripada tindakan Presiden kepada MPR. Padahal MPR tersebut merupakan sebuah lembaga yang bersifat politik/parlemen, bahkan juga ditentukan memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan berupa norma bersifat umum-abstrak yang mengikat umum, yaitu dalam bentuk Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, ternyata pendapat pertama telah menyamakan MPR dengan lembaga perwakilan seperti parlemen. Bahkan diperkuat kembali bahwa seluruh anggota DPR juga merupakan anggota MPR, sehingga mau tidak mau haruslah diakui bahwa secara tidak langsung Presiden bertanggungjawab pula terhadap DPR yang merupakan unsur dari MPR. Sedangkan dilain pihak menurut pendapat kedua, yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut menurut UUD 1945 sebelum
I Gusti Ngurah Santika, SPd
249
diamandemen adalah sistem pemerintahan presidensial murni. Dengan alasan bahwa apa yang dikemukakan oleh pendukung pendapat pertama, dengan menyatakan bahwa MPR adalah sama dengan lembaga perwakilan seperti parlemen adalah tidak benar. Namun, jika dilihat kembali ketentuan tentang pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, terkait dengan kebijakan Presiden yang tidak searah dengan kehendak MPR dalam bentuk garisgaris besar haluan negara. Oleh karenanya MPR dengan alasan tersebut dapatlah kemudian menjatuhkan Presiden dari jabatannya. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis dalam hal ini lebih menyetujui pandapat yang pertama. Selain itu, ditentukan juga bahwa Presiden dan Wakil Presiden sendiri pada waktu itu adalah dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, bahkan tentunya mekanisme pemberhentiannya pun dengan menggunakan suara terbanyak. Jadi, tatacara pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 sebelum diamandemen cenderung menganut sistem pemerintan parlementer. Dengan adanya ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang merupakan hasil daripada amandemen, ternyata telah mampu untuk kemudian lebih menegaskan kembali kedudukan Presiden terutama terkait dengan sistem presidensial menurut UUD 1945, sehingga menjadi semakin jelas. Karena MPR tidak lagi berwenang untuk menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, jika kebijakan yang seblumnya diambil oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ternyata berbeda dengan pandangan MPR, alias neben. Untuk menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya adalah sangat sulit untuk dilakukan, yang tentunya sangat sesuai dengan tujuan daripada sistem pemerintahan presidensial yang kemudian dianut, terutama dengan tujuan agar stabilitas politik terhadap pemerintahan tetap terjaga, sehingga mampu menjalankan semua program kabinet tanpa takut terhadap ancaman parlemen. Tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer di mana seringkali terjadi krisis politik, yang diakibatkan oleh karena sering kali jatuhnya kabinet, disebabkan kabinet tidak mendapatkan dukungan politik dari parlemen. Bahkan sekarang ini, untuk melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak dapat dilakukan hanya oleh satu lembaga negara saja. Dikarenakan dalam konstitusi telah ditentukan dengan tegas mekanisme berkaitan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil akan melibatkan tiga buah lembaga negara, seperti DPR, MK, dan MPR. Adanya ketentuan ini, merupakan upaya penerapan daripada mekanisme checks and balances yang memang sangat diinginkan oleh UUD 1945 setelah diamandemen. Dengan demikian, kekuasaan antara lembaga negara akan saling melakukan pengawasan dan saling mengimbangi, seperti apa yang telah kemudian digariskan dalam UUD 1945. Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, diawali dengan adanya pendapat DPR,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
250
berupa dugaan pelanggaraan hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945 dan/atau DPR kemudian berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Ketentuan yang sama, terkait dengan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diawali dengan usul dari DPR juga terdapat dalam ketentuan Pasal 102 ayat (2) Bab XVII Ketetapan MPR No.1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI tentang Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya. Kemudian untuk menilai objektivitas pendapat DPR tersebut, maka ditetapkan sebuah lembaga peradilan yang kemudian akan menguji pendapat DPR tersebut secara hukum (previlegiatum). Lembaga peradilan sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (constitutional court). Mahkamah Konstitusi lah kemudian menentukan, apakah pendapat DPR, tentang benar atau tidaknya bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah sungguh-sungguh melakukan tindakan berupa pelanggaraan terhadap hukum dan ketentuan lainnya yang sebelumnya telah ditentukan dalam UUD 1945, sebagai mana yang telah didakwakan oleh DPR. Tanpa adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tersebut, yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaraan hukum dan pelanggaran lain menurut UUD 1945, maka upaya DPR untuk melanjutkan proses impeachment akan terhenti atau tidak akan dapat dilanjutkan. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan titik tolah bagi DPR, untuk melanjutkan proses perkara impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden ke MPR untuk selanjutnya diputuskan secara final. Namun, misalkan jika ternyata kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan membenarkan pendapat DPR, terkait dengan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden UUD 1945 atau membenarkan pendapat DPR berkaitan dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka putusan yang kemudian menjadi penentu kata terakhir, apakah Presiden dan/Wakil Presiden diberhentikan atau tidak adalah sangat tergantung pada kehendak MPR sendiri, bukanlah tergantung dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, ditentukan dengan tegas bahwa sebelum MPR mengambil keputusan guna menentukan sikap, apakah akan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan. Dengan demikian, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya, memerlukan proses yang sangat panjang, bahkan dapat dikatakan berliku-liku, yang diawali oleh lembaga politik bernama DPR, sebagai pemohon tunggal yang tentunya sebagai lembaga negara satu-satunya memiliki legal standing, untuk dapat mengajukan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
251
permohonan ke Mahkamah Konstitusi, terkait pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pelanggaran lainnya sesuai dengan UUD 1945. Kemudian berlanjut ke lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi, dan kemudian kembali lagi untuk diputuskan oleh lembaga politik, yaitu MPR, bahkan putusannya tersebut bersifat final. Menurut Syahuri (2011;46) bahwa dengan ketentuan demikian, posisi Presiden menjadi semakin kuat. Dikatakan semakin kuatnya posisi Presiden seperti apa yang kemudian dimaksudkan oleh Syahuri, dikarenakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, untuk sekarang ini telah melibatkan pula suatu lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi, dalam memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ataupun berkaitan dengan pendapat DPR lainnya yang sesuai dengan UUD 1945, tentunya secara tidak langsung membawa sedikit keuntungan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sebelumnya di dakwa. Keuntungan sebagaimana dimaksudkan oleh penulis, dikarenakan hakim-hakim konstitusi yang di dalamnya terdiri dari 9 anggota, yang tiga diantaranya diangkat oleh Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, Presiden jelas-jelas secara politis sudah memiliki 3 suara di Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Presiden hanya tinggal mencari dua suara lagi untuk memenangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Mencari dua suara tentunya lebih mudah, apabila kemudian dibandingkan dengan mempengaruhi 2/3 suara di DPR. Dengan demikian, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan upaya hukum, dalam rangka menegakan prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan, namun dalam prosesnya diwarnai oleh intrik-intrik politis. Bahkan, menurut Mertokusumo (2011;130) terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merupakan suatu forum privelgiatum bahwa pada hakekatnya, forum privelegiatum itu merupakan semacam limited jurisdiction (peradilan khusus/istimewa) bagi orang-orang tertentu, yang ditarik dari peradilan umum dan berfungsi melindungi kepentingan. Memang inilah mungkin yang kemudian dimaksudkan oleh MPR, ketika melakukan perubahan terhadap UUD 1945 terkait dengan sistem pemerintahan presidensial. Bahkan, terkait dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia dipertegas kembali, yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 7C UUD 1945 yang menyatakan bahwa. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat(kursif penulis).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
252
Menurut penulis dimasukannya ketentuan ini merupakan suatu kesepakatan lanjutan untuk memasukan hal-hal yang normatif dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) ke dalam batang tubuh (pasal-pasal) UUD 1945. Sehingga adanya ketentuan ini merupakan hasil daripada kesepakatan MPR RI, sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Dan juga ditambah lagi dengan adanya pengalaman pahit, yang sebelumnya pernah dialami oleh Indonesia, terutama berkaitan dengan keharmonisan hubungan antara Presiden dan lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus secara gamblang menyatakan, bahwa berkaitan dengan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakantindakan Presiden dan Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara, yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggung jawab kepada Presiden. Sistem yang dianut oleh UUD 1945, terkait dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif sebelum UUD 1945 diamandemen pun, sebenarnya menganut suatu mekanisme yang bersifat saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Sistem Undang-Undang Dasar 1945 jelas ada keseimbangan atau checks and balance yang khas antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah, pemerintah kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh DPR (Wilopo dalam Masoed dan Andrews,2006;259). Jelaslah dari bunyi Penjelasan tersebut yang menyatakan bahwa Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, tidaklah memiliki kewenangan untuk dapat membekukan dan/atau membubarkan badan perwakilan. Lembaga perwakilan sebagaimana dimaksudkan adalah DPR, yang tata cara pengisian keanggotaannya adalah dipilih melalui pemilihan umum dengan melibatkan rakyat secara langsung sebagai salah satu persyaratan bagi adanya lembaga ini. Yang tentunya juga sama dengan ketentuan pemilihan Presiden, hanya saja pemilihan umum antara DPR dan Presiden adalah terpisah, berkaitan dengan cara untuk dapat menduduki kedua jabatan tersebut. Hal mana tentunya akan sangat berbeda, apabila kemudian negara tersebut menganut sistem pemerintahannya adalah parlementer. Di mana Presiden selaku kepala negara dapat saja sewaktu-waktu membubarkan badan perwakilan rakyat, yang dalam hal ini adalah parlemen, hanya dengan berbekal saran dari perdana menteri yang menurutnya parlemen sudah tidak mencerminkan kehendak rakyat lagi, sehingga perlu dibubarkan dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
253
kemudian akan diadakan pemilihan umum kembali dalam waktu secepatnya, untuk selanjutnya memilih anggota parlemen yang baru. Ini merupakan salah satu upaya mekanisme checks and balances yang dianut dalam sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet dapat juga dibubarkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya, sebaliknya parlemen dapat pula dibubarkan oleh raja/presiden atas saran perdana menteri. Dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah diamandemen, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, karena secara konstitusional Presiden tidaklah memiliki kewenangan untuk membubarkannya, bedanya sebelum amandemen UUD 1945 ternyata hanya menegaskan kedudukan DPR yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden cuma disebutkan di dalam Penjelasannya, bukan dalam ketentuan Batang Tubuh (pasal-pasal). Namun, setelah perubahan terhadap UUD 1945 dan berakibat pula dengan dihapuskannya Penjelasan UUD 1945, ditambah adanya suatu kesepakatan untuk memasukan hal-hal yang sifatnya normatif ke dalam pasal-pasal UUD 1945, sehingga ketentuan Penjelasan tersebut kemudian disepakati untuk diangkat ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Berkaitan dengan sejarah dari adanya ketentuan tersebut, pernah terjadi ketegangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian diakhiri dengan dibekukannya Dewan Perwakilan Rakyat oleh Presiden. Hal ini terjadi pada zaman pemerintahan Soekarno, dimana terjadi ketidak harmonisan hubungan antara Presiden dan DPR, terutama pada waktu itu adalah berkaitan dengan masalah persetujuan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang mana ketika itu, DPR sebagai lembaga pemegang hak bajet kemudian tidak menyetujui RUU APBN yang telah diajukan oleh Pemerintah. Karena tidak adanya titik temu antara Pemerintah dan DPR, akhirnya Presiden Soekarno membekukan tugas-tugas anggota DPR peralihan, tersebut dengan suatu putusan hukum berupa Penetapan Presiden No.3 Tahun 1960. DPR peralihan ini dibubarkan dengan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 justru karena timbulnya perselisihan antara pemerintah dengan DPR Peralihan ini mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di mana dari 44 miliar rupiah yang diajukan pemerintah hanya disetujui sekitar 36 sampai 38 miliar rupiah saja (Budiardjo,2008;334). Kemudian hal ini, hampir terulang kembali pada era reformasi di mana Gus Dur ketika itu mengeluarkan sebuah Maklumat Presiden, yang pada intinya membekukan MPR dan DPR. Namun, ternyata tindakan Gus Dur tersebut tidaklah sepenuhnya mendapatkan dukungan, khususnya dari Mahkamah Agung, yang menurut maklumat tersebut berwenang memberikan fatwa hukum. Fatwa MA tersebut pada intinya menyatakan bahwa tindakan Presiden yang memutuskan untuk membekukan DPR dan MPR tidaklah memiliki suatu landasan hukum dan tentunya bertentangan dengan UUD 1945. Bunyi dari Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001, yang pada intinya menyatakan,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
254
pertama, membekukan DPR dan MPR RI; kedua, mempercepat pemilihan umum dalam waktu satu tahun; dan ketiga, membekukan Partai Golongan Karya sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung (Ramadhan dalam Soemantri,2006;304). Bedanya, antara tindakan yang diambil oleh Soekarno dengan Gus Dur adalah berkaitan dengan derajat kekuatan daripada keputusan kedua presiden tersebut. Yang dilakukan oleh Soekarno berkaitan dengan pembekuan tugas-tugas daripada anggota DPR, yang berarti bukan membubarkan DPR secara kelembagaan, karena memang secara konstitusional Presiden tidak boleh bertindak demikian. Sedangkan pada masa reformasi, ternyata Gus Dur membubarkan DPR secara kelembagaan dengan cara membekukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh konstitusi. Menurut penulis, adanya ketentuan ini merupakan suatu usaha berupa perlindungan terhadap lembaga perwakilan rakyat, berupa tindakan sewenangwenangan daripada Presiden. Dan hal ini memang sudah terbukti dalam sejarahnya, sehingga merupakan suatu ketentuan wajar, yang kemudian disusul dengan mencantumkannya secara jelas, terkait dengan larangan bagi Presiden untuk berbuat demikian. Sehingga tidak akan ada lagi Presiden dikemudian hari, yang mungkin nantinya mencoba untuk membekukan dan/atau membubarkan DPR. Dan ternyata jika memang dikemudian hari, ada lagi suatu percobaan untuk membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Presiden, tentunya masalahnya ini hanya mungkin dapat diselesaikan secara konstitusional, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, ditentukan selain memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, ternyata juga berwenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang pada dasarnya kewenangan tersebut diberikan oleh UUD 1945. Setelah amandemen terhadap UUD 1945, diatur pula terkait dengan tata cara pengsian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yang apabila diantara kedua jabatannya tersebut terjadi suatu kekosongan, yang dikarenakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden, mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, baik secara bersamaan ataupun karena salah satu di antara kedua jabatan tersebut terjadi kekosongan. Untuk lebih lengkapnya maka penulis akan kutipkan bunyi ketentuan Pasal 8 UUD 1945, yang bunyinya sebagai berikut. 1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
255
2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. 3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya (kursif penulis). Pengaturan tersebut di atas, tentunya sangat jelas berbeda dengan ketentuan yang tercantum sebelum UUD 1945 diamandemen, khususnya berkenaan dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, yang jika kita lihat kembali hanyalah mengatur satu ketentuan, terkait dengan penggantian Presiden yang berhalangan tetap oleh Wakil Presiden, yang kemudian diatur tanpa disertai dengan ayat tambahan. Di samping itu, di sana juga nyatakan bahwa hanya berupa penggantian Presiden dari jabatannya dikarenakan apabila beliau mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, sedangkan ketentuan itu sendiri tidaklah pula mengantisipasi jika seandainya nanti Presiden dan Wakil Presiden bisa saja berhalangan secara bersamaan Sehingga dengan terjadinya peristiwa tersebut tentunya akan mengalami kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dikarenakan memang tidak adanya ketentuan yang mengatur tata cara penggantian dari kedua jabatan yang disebabkan mengalami kekosongan secara bersamaan. Untuk selengkapnya bunyi dari ketentuan Pasal 8 UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu sebagai berikut. Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil sampai habis waktunya (kursif penulis). Apakah yang sebenarnya menyebabkan apabila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, kemudian selanjutnya dapat diganti oleh Wakil Presiden? Tidak lain memang dikarenakan dalam ketentuan UUD 1945 itu sendiri, telah secara tegas diatur dan dicantumkan demikian. Di samping perlu diketahui
I Gusti Ngurah Santika, SPd
256
bahwa tingkat legitimasi antara Presiden dan Wakil Presiden adalah sama, dikarenakan kedua jabatan tersebut adalah dipilih secara langsung oleh rakyat, bahkan jika dikehendaki oleh Presiden, yang disebabkan oleh berbagai hal yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka Presiden dapat saja selanjutnya menyerahkan, baik hanya untuk sementara waktu saja berkenaan dengan tugasnya tersebut kepada Wakil Presiden sebagai pembantunya. Ini dapat diartikan apabila suatu saat Presiden berhalangan menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, maka Wakil Presiden dapat melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan Presiden untuk sementara waktu. Hal itu dimungkinkan oleh karena, baik Presiden maupun Wakil Presiden, dipilih dengan syarat-syarat dan prosedur yang sama (Soemantri,1985;18). Bahkan, jika memang dikemudian hari ternyata Presiden berhalangan tetap, maka Wakil Presidenlah yang kemudian naik dan menggantikan kedudukannya secara konstitusional menjadi Presiden. Sedangkan untuk sekarang ini, menurut ketentuan Pasal 8 UUD 1945 setelah diamandemen, telah membuka peluang kepada pembantu Presiden, yaitu kepada tiga menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan, untuk menjadi pelaksana tugas kepresidenan yang tentunya bersifat sementara waktu, tentunya dengan syarat apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan. Namun, konstitusi telah menentukan batasan waktu terkait sebagai pelaksana tugas kepresidenan, yaitu menterimenteri dimaksudkan tersebut di atas hanya dapat melaksanakan tugas kepresidenan dalam waktu selama-lamanya adalah tiga puluh hari. Lebih lanjut konstitusi juga telah menentukan bahwa MPR kemudian harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tentunya siapakah yang kemudian akan dipilih menjadi Presiden oleh MPR? Dalam konstitusi ditentukan pula bahwa yang dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik sebagai pemenang pertama dan kedua pemilihan umum sebelumnya. Jadi pada intinya yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ke MPR adalah partai yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua pemilihan umum sebelumnya. Ketentuan yang sama dapat kita jumpai kembali dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009, yang menyatakan : Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya (kursif penulis).Tentunya, siapa yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang baru, akan sangatlah tergantung dari dukungan suara dari anggota MPR. Tentunya dalam hal ini adalah kursi dimiliki oleh partai politik/gabungan partai politik di MPR akan sangat berpengaruh terhadap kemenangan daripada calon Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya diajukan oleh partai politik
I Gusti Ngurah Santika, SPd
257
atau gabungan partai politik. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk memperhitungkan kembali peta kekuatan politik yang dimiliki oleh partai politik tertentu, terutama partai politik yang duduk MPR. Jadi, suara di MPR yang sebelumnya dikuasai oleh partai politik mayoritas dengan bukti berupa penguasaan kursi, tentunya sudah dapat dipastikan kemudian akan keluar serta menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemenangnya. Dalam UUD 1945 tepatnya ketentuan di Bab V tentang Kementerian Negara, dalam kenyataannya mengalami amandemen. Ketentuan Pasal 17 yang di dalamnya terdiri dari 4 ayat secara lengkap bunyinya, yaitu. 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang (kursif penulis). Sebelum ketentuan Pasal 17 UUD 1945 diamandemen, maka berkaitan dengan pengaturan kementerian negara dalam UUD 1945 di dalamnya terdiri dari 3 ayat, yang bunyinya, yaitu sebagai berikut. 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. 3. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan (kursif penulis). Apabila kita cermati kembali isi daripada ketentuan Pasal 17 UUD 1945 setelah perubahan, yang di dalamnya pengaturannya secara tegas menetapkan pula tentang kedudukan menteri dalam UUD 1945, yang sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Bahkan berasarkan pasal-pasal yang sebelum dibahas berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden di dalam UUD 1945, pada dasarnya semuanya diatur sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kemudian Wiyono (2009;18) mengemukakan pendapatnya, terkait dengan ciri daripada sistem pemerintahan presidensial, yang menurutnya bahwa: Apabila konsekuensi dengan isi pasal tersebut, maka sudah semestinya diikuti pula tolok ukur sistem pemerintahan presidensial yang antara lain: (1) kekuasaan bersifat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
258
tunggal (tidak bersifat kolegial) baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan; (2) kedudukan Presiden dan parlemen sama kuatnya dan tidak bisa saling menjatuhkan; (3) masa jabatan Presiden bersifat pasti (fix-term), tidak dapat diberhentikan kecuali melanggar konstitusi; (4) Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen, tetapi bertanggungjawab kepada rakyat; (5) Presiden dipilih rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden; (7) pertanggungjawaban pemerintahan berada di tangan presiden. Maka adalah hak Presiden untuk menentukan orang-orang yang akan bertindak sebagai pembantunya (Mahkamah Konstitusi,2010;936,Jilid II). Dalam pasal ini Presiden diberikan kewenangan yang bersifat prerogatif, artinya hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam hal menentukan kebijaksanaan atau pembentukan kabinet, baik personalia(Handayaningrat,1986;32). Dengan demikian, tentunya berbeda dengan negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, yang keanggotaan kabinet diangkat berdasarkan keanggotaannya di lembaga legislatif, bahkan dipersyaratkan untuk menjadi anggota menteri haruslah juga terpilih dan duduk sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu, tentunya terpilihnya menjadi seorang menteri adalah tergantung dari partai politik yang memiliki dukungan paling besar, yang kemudian dibuktikan kembali dengan dukungan kursi di parlemen, maka partai politik tersebutlah yang selanjutnya berwenang untuk membentuk kabinet atas restu raja/presiden. Berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 17 tersebut, menurut Simanjuntak (1981;20) bahwa menteri merupakan pembantu Presiden sehingga dengan demikian Presiden tidak membutuhkan contra sign dari menteri apabila Presiden mengeluarkan peraturan perundangan. Karena, Presidenlah sebagai kepala pemerintahan yang memegang kata kunci dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya berkaitan dengan tugas-tugasnya, walaupun dalam kenyataannya bisa saja kemudian diwakilkan kepada menteri. Namun menteri tersebut hanyalah datang untuk mewakili daripada kehendak Presiden, sehingga pertanggungjawabannya tetaplah berada pada pundak Presiden. Presidenlah kemudian yang akan menentukan siapakah orang-orang dipandang dapat untuk ditempatkan dalam pos-pos kementerian yang sebelumnya telah tersedia sesuai dengan kecakapannya. Selain itu, juga diharapkan nantinya bahwa menteri tersebut tentunya akan selalu loyal dan patuh, terhadap semua perintah yang kemudian diberikan oleh Presiden, sebagai seorang yang sebelumnya telah menunjuknya/mengangkatnya sebagai menteri. Kewenangan untuk membentuk kabinet yang tidak berdasarkan pada
I Gusti Ngurah Santika, SPd
259
konstelasi kekuatan politik daripada parlemen, dikarenakan bahwa Presiden dipilih melalui pemilihan umum, yang tentunya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga, untuk menentukan pembantu-pembantunya haruslah atas kehendak Presiden sendiri. Relevan untuk selanjutnya dikutip dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 17 tersebut, yang menyatakan bahwa: Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden (kursif penulis). Dengan demikian, jelaslah bahwa alur pertanggungjawaban menteri adalah kepada Presiden bukannya kepada parlemen, dikarenakan telah ditentukan bahwa Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden (concentration of power and responbility upon the president). Tidak lain dikarenakan Presiden yang merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara dalam sistem pemerintahan presidensial, adalah dipilih oleh rakyat secara langsung, sehingga tidaklah ia ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya berkaitan dengan tugas-tugasnya kepada DPR. Dalam pada itu, Presiden yang sebelumnya dipilih oleh rakyat secara langsung, juga tentunya berwenang untuk mengangkat menteri, yang memang merupakan suatu kelazimanm terutama dalam sistem pemerintahan presidensial. Tentunya yang kemudian menjadi pertimbangan utama, untuk bisa menempatkan seseorang menjadi menteri adalah dengan mengangkat orang-orang yang benar-benar dianggapnya ahli, terutama dalam bidang tugas yang kelak diembannya. Hal ini tentunya sejalan dengan dianutnya sistem pemerintahan presidensial, di mana bukannya faktor politik yang paling menentukan untuk pengangkatan seorang menteri, namun keahlian yang kemudian menjadi dasar utama sebagai pertimbangannya. Sehingga hanya orang ahli yang nantinya benar-benar diperlukan dan menguasai bidangnya, kemudian dapat terpilih dan mengisi kedudukan sebagai menteri, sehingga sungguh-sungguh mampu untuk membantu Presiden, terutama dalam menjalankan tugasnya yang sangat berat. Pernyataan tersebut adalah sangat sesuai dengan pendapat yang dikemukakan, oleh Mahmud MD (2009;108) yang kemudian menyatakan bahwa untuk lembaga eksekutif sistem pemilihan Presiden secara langsung harus disertai dengan instrumen atau subsistem rekruitmen pejabat yang mendorong Presiden membentuk zaken kabinet (kabinet ahli, bersih, dan profesional) dengan membebaskan Presiden dari
I Gusti Ngurah Santika, SPd
260
belenggu untuk melakukan itu, karena transaksi politik, kompensasi, dan dukungan parpolparpol. Selain itu, diharapkan menteri-menteri tersebut setelah ditujuk kemudian, haruslah selanjutnya dapat berkerjasama sebaik-baiknya dengan Presiden, maupun dengan sesama menteri lainnya dalam kabinet. Sebenarnya ini pun sejak semula telah disadari pula, oleh para pendiri negara (founding father), yang kemudian dinyatakan di dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, yang bunyinya: Meskipun kedudukan menteri negara tergantung daripada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executif) dalam praktek Sebagai pemimpin departemen, menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan itu, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Memang yang dimaksudkan ialah, para menteri itu memimpinmemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja bersama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden (kursif penulis). Dari penjelasan di atas, maka dapatlah kemudian ditangkap bahwa menteri dalam kenyataannya memegang peranan yang sangat besar dan menentukan, terutama untuk menyukseskan program kabinet, yang sebelumnya memang telah digariskan oleh Presiden sebagai atasannya. Karena berdasarkan pertimbangan itulah, mengapa menteri itu haruslah kemudian diangkat dari orang-orang yang memang profesional, serta benar-benar ahli dalam bidang tugas yang akan diembannya kelak. Tentunya Presiden dalam membentuk kabinet dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang ini, pastinya akan membentuk kabiet yang benar-benar zaken kabinet (kabinet ahli), tanpa memperdulikan konstelasi kekuatan politik, yang bisa saja sewaktu-waktu mempengaruhinya, termasuk dari lembaga legislatif terutama oleh partai politik, pada saat memutuskan untuk mengangkat maupun memberhentikan menteri. Perubahan terhadap ketentuan ayat (2) dari Pasal 17 UUD 1945, yaitu hanya mengganti kata diperhentikan kemudian menjadi diberhentikan adalah menyesuaikan dengan tata bahasa Indonesia, sehingga setelah dirubah menjadi sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Selain itu, telah ditentukan pula bahwa setiap menteri memegang urusan tertentu dalam pemerintahan. Adanya ketentuan tersebut tidaklah terlepas dari perjalanan sejarah sebelumnya, yang menyatakan bahwa menteri haruslah memimpin suatu departemen, sedangkan dalam kenyataannya banyak menteri yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
261
kemudian tidak memimpin departemen. Bedasarkan pertimbangan itulah, maka perlu dirubah dengan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, urusan tertentu merupakan ketentuan yang sifatnya fleksibel, karena kemudian bisa saja diberikan tafsiran sesuai dengan keperluan di lapangan. Berkaitan dengan kata urusan tertentu dalam ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, perlulah diatur kembali oleh Presiden dan DPR, dalam bentuk undang-undang yang nantinya tentu harus menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Juga ditegaskan dalam ketentuan ayat (4) dari Pasal 17 (UUD 1945, bahwa dalam hal pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara haruslah diatur dalam undang-undang. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa tidaklah mudah kemudian bagi seorang Presiden untuk membentuk kementerian ataupun mengubah kementerian, seperti pada zaman Soekarno yang sering kali membentuk kementerian baru dan mengubahnya sesuai dengan kemauannya. Terkait dengan pembubaran kementerian harus juga diatur kembali dalam undang-undang, adanya ketentuan ini merupakan suatu evaluasi mendalam terhadap pemerintahan. Terutama dengan pengalaman pada era reformasi, di mana Presiden Abdurahman Wahid ketika itu berani membubarkan kementerian penerangan, yang mana telah menyebabkan kesulitan terutama terhadap tugas-tugas yang dulunya diemban oleh kementerian tersebut, selainnya adanya masalah lainnya, misalnya, berkaitan dengan kepegawaiannya. Kenyataan ini memang pada awalnya dapat dilihat ketika Gus Dur terpilih menjadi presiden banyak pimpinan partai, pakar, dan pengamat mengharapkan dibentuknya sebuah kabinet yang ramping, solid dan profesional agar mampu membawa warga negara ini keluar dari krisis. Namun, untuk sekarang, implikasi dari adanya ketentuan ini, terutamanya berkaitan dengan kelembagaan kementerian, haruslah kemudian dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR, yang kemudian akan disepakati dalam bentuk undang-undang. Namun dalam hal menentukan orangnya/menterinya, adalah tetap masih merupakan hak prerogarif Presiden, hanya saja berkaitan dengan kelembagaan, perlu kemudian untuk diatur kembali secara bersama antara Presiden dan DPR. Tidak lain, adanya ketentuan ini, dapatlah selanjutnya dikaitkan dengan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh DPR, terutama dalam bidang pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang semua hal tersebut di atas tentunya sangat mempengaruhi bidang anggaran keuangan negara. Setidaknya, jika saja nantinya bertambah ataupun berkurangnya kementerian, tentunya akan sangat berpengaruh dengan anggaran keuangan negara, padahal anggaran keuangan negara merupakan uang rakyat, yang jikalau digunakan harus terlebih diketahui sendiri oleh rakyat sebagai pemiliknya, untuk dapat memberikan persetujuan, yaitu melalui wakilwakilnya yang duduk di DPR. Sehingga untuk itu, DPR perlu duduk bersama dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
262
pemerintah, agar dapat memutuskan kembali tentang pengaturan kementerian dalam bentuk undang-undang, yang tentunya di sini berkaitan erat dengan masalah pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara, yang tentu nantinya akan sangat mempengaruhi uang rakyat, yakni APBN. Kekuasaan Presiden atas angkatan Darat, angkatan Laut dan Udara ternyata tidaklah mengalami perubahan dalam UUD 1945, sebagaimana dapatlah kemudian kita ketahui, hanya dengan membandingkan antara ketentuan sebelum dan sesudah amandemen terhadap UUD 1945, mengenai pengaturan sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas. Dalam ketentuan Pasal 10 UUD 1945, dinyatakan bahwa. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (kursif penulis). Siapakah dalam hal ini yang dimaksudkan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam ketentuan Pasal 10 UUD 1945? Untuk kemudian dapat menjawabnya, maka telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945, berupa jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, yang selanjutnya dalam pasal tersebut menyatakan, bahwa. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (kursif penulis). Dengan adanya ketentuan Pasal 10 UUD 1945 tersebut, maka Presidenlah yang memegang otoritas dan kendali untuk kemudian mengerahkan seluruh kekuatan, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, terutama dengan tujuan untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 30 UUD 1945. Bahkan, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia, yang selanjutnya menyatakan bahwa Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden(kursif penulis). Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) pada undang-undang yang sama dinyatakan bahwa. 1. Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
263
2. Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 18 (1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. (2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut (kursif penulis). Tugas Presiden yang berkaitan dengan hubungan internasional, terutama yang menyangkut kehidupan nasional, pada dasarnya adalah menyangkut masalah-masalah yang cukup sensitif bagi kehidupan bangsa, yang kemudian dibuat Presiden, misalnya dalam bentuk pernyataan perang, perjanjian, atau mengakibatkan perubahan pada undang-undang, tentunya memerlukan bantuan dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan pemegang kekuasan dalam bidang pembentukan undang-undang. Hal mana telah ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 11 UUD 1945, yang berbunyi, antara lain: 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamain dan perjanjian dengan negara lain. 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang. Sebelumnya, dalam ketentuan Pasal 11 UUD 1945 tentang Perjanjian Internasional, pada intinya pengaturan tersebut hanya terdiri dari satu ketentuan saja, kemudian tanpa dilengkapi dengan ayat. Bunyi dari ketentuan Pasal 11 UUD 1945 sebelum diamandemen, yaitu. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
264
Dengan adanya amandemen terhadap ketentuan Pasal 11 UUD 1945, untuk sekarang dalam kenyataannya ketentuan ini telah dilengkapi dan ditambah dengan 3 ayat. Selain itu, ternyata untuk substansinya juga tidak ada perubahan, karena dalam ketentuan Pasal 11 UUD 1945 sebelum diamandemen, hanyalah dirubah penomoran ayatnya saja. Bahkan, dalam kenyataannya ditambah lagi dengan dua ayat, sehingga keseluruhannya menjadi tiga ayat. Menurut MPR RI (2011;103) bahwa Pasal 11 (naskah asli) dirumuskan dalam suasana ketika perjanjian internasional yang ada pada saat itu lebih banyak berbentuk perjanjian antar negara, sementara saat ini perjanjian internasional bukan hanya perjanjian antara negara tetapi juga antara negara dengan kelompok negara atau antara negara dengan subjek hukum internasional lain yang bukan negara atau badan-badan internasional, misalnya organisasi internasional, Palang Merah Internasional, dan Tahta Suci, yang tentunya dapat membawa implikasi yang luas di dalam negeri. Tentunya kemudian dengan adanya ketentuan ini, maka tindakan Presiden yang menyangkut dan dapat saja mengurangi hakhak rakyat, terutama dalam hubungannya dengan tujuan untuk mencapai kehidupan bernegara, seperti adanya pernyataan perang, yang tentu pastinya kemudian akan mengurangi hak rakyat dalam menikmati keamanan dan kenyamanan, bahkan bisa jadi diharuskan untuk memikul senjata, guna membela kepentingan negara. Semua hal tersebut haruslah terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri, melalui wakilwakilnya yang kemudian duduk di DPR. Sesuai dengan perkembangan hukum internasional seperti sekarang ini, pemerintah sering pula melakukan perjanjian terkait hutang dan piutang, baik dengan organisasi internasional seperti IMF dll. Tindakan tersebut tentunya akan berdampak luas, yang bahkan bisa saja mengurangi hak-hak rakyat dalam menikmati uangnya, karena diharuskan untuk ikut menanggung serta membayar utang, yang sebelumnya dipinjam oleh pemerintah kepada lembaga keuangan tersebut. Untuk itu, pastinya kemudian DPR sebagai lembaga negara yang terdiri dari wakil-wakil rakyat, untuk selanjutnya dapat saja memberikan persetujuan, sesuai dengan ketentuan daripada UUD 1945. Untuk itu, tindakan Presiden berkaitan dengan pernyataan perang yang pada hakekatnya dapat mengancam jiwa rakyat dan juga berkaitan dengan keuangan negara, yang tentu nantinya dapat dipastikan akan memberatkan rakyat dikemudian hari, haruslah terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena DPR notebane merupakan wakil-wakil rakyat, untuk selanjutnya berusaha sekuat tenaga, sehingga ke depannya mampu memperjuangkan nasib rakyat yang benar-benar menderita, oleh karena kebijakan yang kemudian diambil oleh pemerintah. Pengaturan berkaitan dengan pernyataan perang, sebenarnya sudah terdapat dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang pada dasarnya mengatur tentang pernyataan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
265
perang oleh Presiden, yang kemudian untuk selanjutnya haruslah mendapatkan persetujuan kembali daripada DPR. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya, pada dasarnya adalah menyangkut masalah yang sifatnya prinsipil dan mendasar, bahkan memiliki akibat luas, terutama bila berkaitan dengan hak-hak rakyat dan keuangan negara. Keuangan negara sendiri merupakan sarana yang diperuntukan untuk menyejahterakan rakyat, ataupun berkaitan dengan keperluan negara lainnya. Namun, sewaktu-waktu yang disebabkan oleh suatu keadaan, kemudian bisa saja kita memerlukan bantuan uang, berupa dalam bentuk utang yang kemudian diberikan oleh negara lain maupun lembaga keuangan internasional yang memang dibentuk untuk itu. Semua peristiwa tersebut, haruslah mendapat persetujuan dari rakyat sendiri, hal mana dikarenakan bahwa rakyatlah secara tidak langsung, kemudian nantinya akan mengembalikan utang negara tersebut, entah melalui pajak yang kemudian dipungut oleh negara, karena tentunya rakyat sendirilah yang nantinya akan menjadi subjek pajak. Apalagi perjanjian internasional tersebut, ternyata juga menyangkut masalah, perubahan dan/atau pembentukan undang-undang, tentu pastinya sudah seharusnya mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pernyataan tersebut tentunya sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yang pada dasarnya telah menggariskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan wakil rakyat adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Walaupun nantinya sebelum menjadi undang-undang, tentunya harus mendapat persetujuan pula dari kedua belah pihak (Presiden dan DPR), agar perubahan dan/atau pembentukan undang-undang tersebut, kemudian dapat sah menjadi undang-undang yang mengikat rakyat. Dengan demikian, DPR lah kemudian yang akan meratifikasi perjanjian internasional, agar kela dapat efektif berlaku di wilayah huku negara Indonesia. Untuk sekarang, sudah ada suatu ketentuan berupa Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang merupakan suatu ketentuan hukum untuk mengatur lebih lanjut, tentang perjanjian internasional, sebagaimana yang kemudian dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) UUD 1945. Di dalamnya pun sudah diatur berkaitan dengan masalah-masalah apa saja, yang hendaknya perlu untuk diatur kembali dalam bentuk undang-undang, terutama yang nantinya akan dibentuk melalui perjanjian Internasional. Kemudian dalam UU No. 24 Tahun 2000 tepatnya pada Bab III yang mengatur mengenai Pengesahan Perjanjian Internasional, yang dalam ketentuan Pasal 10 undang-undang tersebut, menyatakan bahwa berkaitan dengan pengesahan suatu perjanjian internasional, dilakukan dengan bentuk undang-undang apabila berkenaan dengan:
I Gusti Ngurah Santika, SPd
266
a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. Pembentukan kaidah hukum baru; f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Selain materi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 10 UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, barulah dapat kemudian bagi Presiden untuk mengaturnya sendiri, bahkan tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari DPR. Bahkan, pengaturan perjanjian Internasional selain sebagaimana dimaksudkan di atas, dapatlah kemudian dilakukan sendiri oleh Presiden, hanya dengan bentuk hukum berupa suatu Keputusan Presiden. Hanya saja agar kelak tidak ada suatu ketentuan berupa perjanjian internasional, yang seharusnya diatur kembali dalam bentuk undang-undang. Namun, dalam kenyataannya bisa saja nanti Presiden malah mengaturnya dalam bentuk Keputusan Presiden, entah mungkin saja dikarenakan Presiden merasa kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari DPR, sehingga kemudian hanya meratifikasinya dengan bentuk hukum berupa Keputusan Presiden. Untuk itu, dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, tepatnya ketentuan dari Pasal 11, pada dasarnya menyatakan bahwa: Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi (kursif penulis). Ketentuan tersebut adalah sesuai dengan pendapat Ardhiwisastra (2003;144-145) yang menyatakan bahwa untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan DPR sebagai dimaksudkan dalam Pasal 11 UUD 1945, Pemerintah akan menyampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuannya hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja (treaties), sedangkan perjanjian lain (agreement) akan disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui saja. Perlu diketahui kembali, bahwa meratifikasi suatu perjanjian berarti bahwa negara yang bersangkutan telah mengikatkan diri untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dan bahwa ketentuanketentuan tersebut kemudian menjadi bagian daripada hukum nasionalnya (Budiardjo,2008;226,Mahmud MD,2010;205, Winarno,2009;140). Selain dalam ketentuan Pasal 10 UUD 1945, yang pada dasarnya tidaklah mengalami perubahan, ternyata ada juga satu ketentuan lainnya, terutama berkenaan dengan ketentuan Pasal 12 UUD 1945 tidaklah mengalami perubahan, bunyi pasal tersebut, yaitu sebagai berikut.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
267
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (kursif penulis). Dengan adanya ketentuan ini, jika suatu saat dimana negara dalam keadaan bahaya, maka atas dasar situasi dan kondisi tersebut Presidenlah yang selanjutnya berwenang untuk menyatakan hal tersebut. Namun perlulah diketahui bahwa terkait pernyataan Presiden yang menyatakan negara dalam keadaan bahaya, tidaklah dapat dinyatakan oleh Presiden secara sepihak. Dengan demikian, tentunya akan berbeda pula dengan makna daripada ketentuan Pasal 22 UUD 1945, yang mengisyaratkan hal ihwal kegentingan memaksa, dalam pada itu tentunya tidak ketahui sebelumnya atau belum dapat diperkirakan, maka Presiden untuk itu dapat mengambil inisiatif berupa tindakan secara sepihak, dengan menyatakan bahwa ada situasi yang genting, bahkan memaksanya, untuk kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 12 UUD 1945, untuk syarat-syarat menyatakan negara keadaan bahaya serta akibatnya, sudah terlebih dahulu ditetapkan dengan tegas dalam undang-undang, sehingga berdasarkan kriteria yang sifatnya jelas tersebut, yang kemudian diatur kembali dalam bentuk undang-undang, sehingga barulah Presiden berhak untuk menyatakan keadaan bahaya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 UUD 1945. Amandemen UUD 1945, menyebabkan pula perubahan yang sangat mendasar dan prinsipil terkait dengan pengertian mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Presiden, termasuk juga hak prerogatif yang sebelumnya dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 13 UUD 1945 setelah perubahan yang berbunyi. 1. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (kursif penulis). Sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, khususnya terhadap ketentuan Pasal 13, yang sebelumnya terdiri dari dua ayat, namun tentunya akan berbeda pengertiannya dengan ketentuan setelah adanya perubahan terhadap pasal tersebut. Rumusan asli naskah Pasal 13 UUD 1945 sebelum diamandemen adalah sebagai berikut. 1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
268
2.
Presiden menerima duta negara lain.
Duta memiliki tugas yang sangat penting, bahkan memiliki pengaruh yang tidak kecil, terutama terhadap negara yang diwakilinya. Tentunya tidak sembarangan orang dapat diangkat untuk menjadi duta negara, setidaknya orang tersebut, adalah orang mampu dan cakap untuk mengemban tugas dan kewajibannya menjadi duta negara, yang nantinya akan menjalankan tugas-tugas kenegaraan, yang telah ditentukan untuk menjadi wewenangnya. Dengan alasan tersebut, diharapkan Presiden yang kemudian mengangkat duta negara lebih obyektif, terutama dalam menentukan kriteria untuk menjadi seorang duta negara, maka dipandang perlu untuk selanjutnya didengar terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum Presiden sendiri yang kemudian memutuskannya. Adanya ketentuan ini merupakan salah satu bentuk mekanisme Checks and balances antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya. Bahkan tidak hanya dalam pengangkatan duta negara saja, yang ditentukan perlu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, ternyata dalam masalah menerima penempatan duta negara lain pun, Presiden harus pula memperhatikan pertimbangan DPR, meskipun ketentuan ini tidaklah lazim dalam hubungan internasional. Namun, pertimbangan-pertimbangan yang kemudian diberikan oleh DPR kepada Presiden tersebut di atas, tidaklah bersifat mengikat secara yuridis, tetapi tentunya perlu untuk diperhatikan secara politis. Bahkan, adanya pertimbangan DPR ini merupakan suatu kerangka untuk melaksanakan salah satu fungsi dari DPR, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Bahkan, terkait dengan hal tersebut menurut penulis memiliki implikasi politis, yang pastinya memiliki dampak yang luas terhadap semua kebijakan Presiden lainnya, dalam hubungannya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, terutama bilamana kebijakan lainnya tersebut bersentuhan dengan fungsi dan kewenangan DPR. Hal mana jika dalam suatu masalah tertentu, kemudian Presiden ternyata tidaklah mendengar pertimbangan DPR dengan sungguh-sungguh, dapatlah dipastikan akan berimplikasi luas terhadap penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, apalagi kebijakankebijakan Presiden tersebut bersentuhan dengan DPR sebagaimana dimaksud di atas. Kemudian dapatlah diketahui untuk sekarang ini adalah sangat banyak wewenang Presiden, namun dalam kenyataannya memerlukan keterlibatan DPR, yang memang telah ditentukan secara tegas dalam konstitusi, baik yang kemudian dalam bentuk pertimbangan maupun persetujuan. Berkaitan dengan hak prerogatif Presiden kemudian diatur kembali mengenai pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Sebelum adanya amandemen terhadap
I Gusti Ngurah Santika, SPd
269
UUD 1945, ketentuan tentang pemberian grasi, amnesti, rehabilitasi hanya diatur dalam satu pasal tanpa disertai ayat. Hal mana dapatlah diketahui kemudian dalam ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan, yang berbunyi. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (kursif penulis). Sedangkan untuk sekarang ini, Presiden tidaklah dapat seleluasa seperti dulunya dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Karena untuk sekarang ternyata diperlukan suatu pertimbangan dari lembaga negara lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung sebagai wujud utama saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antara lembaga negara. Setelah adanya terhadap amandemen UUD 1945, khususnya terhadap ketentuan Pasal 14, dimana sebelumnya hanya terdiri dari satu pasal tanpa kemudian disertai dengan ayat, namun untuk sekarang setelah perubahan telah ditambah lagi dengan dua ayat. Berikut ini merupakan ketentuan lengkap Pasal 14 UUD 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Presiden memberi grasi pertimbangan Mahkamah Agung. dan rehabilitasi dengan memperhatikan
2.
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kewenangan Presiden, dalam memberikan grasi termuat dengan jelas dalam ketentuan Pasal 14 UUD 1945, maka untuk itu perlulah diberikan pengertian, agar mendapatkan sedikit kejelasan. Pada umumnya, setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jaksa pada kesempatan pertama akan melakukan eksekusi (Pasal 270 KUHAP). Namun, ada kalanya jaksa tidak dapat melakukan eksekusi atau hak eksekusi telah habis, sehingga putusan yang telah berkekuatan tetap tidak dapat dilakukan untuk selama-lamanya. Hal ini dikarenakan oleh berbagai hal, seperti kematian terpidana, daluwarsa (Pasal 84 KUHP), selain adanya ketentuan tersebut ternyata dalam UUD 1945 juga telah ditentukan adanya pemberian grasi oleh Presiden. Bahwa untuk mendapatkan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepada Presiden. Dalam Penjelasan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010 bahwa Kata dapat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
270
grasi sesuai dengan Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah : (1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UndangUndang tentang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981); (2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UndangUndang tentang Hukum Acara Pidana; atau (3) putusan kasasi. Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana. Grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi). Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh hukuman yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi hukuman, atau menukar hukuman pokok berat dengan suatu hukuman yang lebih ringan (Marpaung,2009;104). Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun (lihat ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010). Jika kita lihat kembali sebelum adanya UU No. 5 Tahun 2010, maka pengertian Grasi menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang dijelaskan kemudian dalam pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan, untuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, dilakukan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikembalikan kepada kedudukannya. Dasar pemikiran adanya grasi yang diberikan oleh eksekutif adalah mengingat bahwa tidak ada pengadilan yang sempurna dan sekalipun terbuka kesempatan banding dan kasasi, maka demi keadilan dirasakan masih perlu koreksi terhadap putusan-putusan pengadilan (Mertokusumo,2011;133). Dahulu, grasi ini merupakan hak raja sehingga dianggap sebagai anugerah raja. Akan tetapi, pada saat ini grasi merupakan suatu alat untuk menghapuskan sesuatu yang dirasakan jika hukum yang berlaku menimbulkan kekurangadilan (Merpaung,2009;104).Walaupun seperti terlihat bahwa eksekutif memiliki kekuasaan untuk campur tangan terhadap peradilan, namun hanya saja bukan dalam prosesnya, tetapi dalam bentuk pembatalan keputusan peradilan yang sudah memiliki kekuatan tetap.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
271
Biasanya ada berbagai alasan-alasan yang dimuat dalam peraturan perundangundangan untuk hapusnya hak penuntutan seperti adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHP), kematian orang melakukan delik (Pasal 77 KUHP), daluwarsa (Pasal 78 KUHP), dan penyelesaian perkara di luar persidangan (Pasal 82 ayat (1) KUHP). Selain adanya alasan tersebut di atas, dalam peraturan perundangundangan (bukan KUHP), masih juga ada ketentuan yang dapat menghapuskan hak untuk melakukan penuntutan atas pelaku kejahatan, yakni abolisi dan amnesti. Pada dasarnya ketentuan kedua hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden, namun tetap dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Sedangkan untuk pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Sedangkan menurut Merpaung (2009;103) bahwa abolisi adalah penghapusan hak untuk melakukan penuntutan pidana dan menghentikan penuntutan pidana yang telah dimulai. Adapun amnesti adalah pernyataan pengampunan atau penghapusan hukuman kepada umum yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Baik abolisi maupun amnesti merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum atau untuk mencegah korban yang lebih besar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya diatas, Presiden dalam memberikan baik grasi dan rehabilitasi telah ditentukan dalam UUD 1945, dalam kenyataannya memerlukan bantuan dari lembaga negara lainnya, yaitu dalam bentuk pertimbangan dari Mahkamah Agung, di mana tentunya pertimbangan yang kemudian diberikan oleh MA adalah pertimbangan hukum, karena Mahkamah Agung sendiri merupakan salah satu lembaga yang memang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan. Namun, tidaklah berbeda jauh kekuatan mengikat dari pertimbangan yang sebelumnya diberikan oleh DPR kepada Presiden, maka pertimbangan yang kemudian diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden, ternyata tidaklah mengikat secara hukum. Jadi Presiden dapat saja untuk mengikuti pertimbangan dari Mahkamah Agung ataupun tidak mengikuti pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung, semuanya tergantung daripada kehendak Presiden sendiri. Hal mana juga berlaku terhadap pertimbangan yang diberikan oleh DPR terhadap Presiden, berkaitan dengan pemberian amnesti dan abolisi. Tidak lain tujuan dari adanya pertimbangan MA dan DPR, merupakan suatu pembatasan yang bersifat ketatanegaraan, terutama dalam rangka menjalankan mekanisme check and balances terhadap kekuasaan Presiden, sebagaimana juga dengan tugas-tugas tersebut di
I Gusti Ngurah Santika, SPd
272
atas. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak mengurangi hal-hal yang esensial yang seharusnya ada dalam sistem pemerintah presidensial (Asshiddiqie,2009;300) Kemudian kewenangan Presiden dalam rangka memberikan tanda kehormatan diatur dengan undang-undang, yang mana dalam hal ini secara tidak langsung juga melibatkan DPR, terkait dengan kewenangan Presiden memberikan tanda kehormatan melalui undangundang yang selanjutnya dibuat bersama. Sehingga, tentunya akan berbeda dengan ketentuan sebelum adanya perubahan UUD 1945, di mana ketika itu Presidenlah yang secara mutlak memberikan tanda kehormatan atau dengan kata lain merupakan suatu hak prerogatifnya. Dalam ketentuan Pasal 15 UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi. Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (kursif penulis). Sedangkan setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 15, yang dalam kenyataannya mengalami suatu perubahan, sehingga kemudian ketentuan tersebut di atas menjadi berubah bunyinya, yaitu sebagai berikut. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut secara tegas mengamanatkan pembentukan undang-undang yang mengatur kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Rumusan pasal tersebut mengamanatkan kepada Presiden agar dalam memberikan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kepada WNI, kesatuan, institusi pemerintah, organisasi, ataupun WNA mempertimbangkan aspek kesejarahan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, bobot perjuangan, karya, prestasi, visi ke depan, objektif, dan untuk mencegah kesan segala bentuk dikotomi. Perlunya pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan oleh Presiden setidaknya didasari oleh berbagai pertimbangan. Bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah di darmabaktikan bagi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh negara dalam bentuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
273
gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan darmabakti kepada bangsa dan negara. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dinyatakan bahwa Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Dalam ketentuan ayat (2) dari Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. Dalam ketentuan ayat (3) dari Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Dengan terbentuknya Undang-Undang ini, pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh Presiden sebagai kepala negara mempunyai landasan hukum yang lebih kuat dan kepastian hukum yang lebih terjamin. Seluruh pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dicantumkan dalam bagan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang ini. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan 4 (empat) kali berturut-turut sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah membawa perubahan yang mendasar, terutama di berbagai bidang kehidupan ketatanegaraan. Perubahan tersebut, antara lain, menyangkut penataan kembali kelembagaan negara, baik berupa penghapusan atau pembentukan lembaga baru maupun pendefinisian ulang tugas, fungsi, dan kedudukan lembaga negara. Selain, adanya ketentuan yang baru dalam UUD 1945, juga dihapuskannya beberapa ketentuan yang ada dalam UUD 1945, seperti adanya lembaga-lembaga negara baru yang kemudian dibentuk, namun dilain pihak ternyata ada suatu keputusan berupa penghapusan terhadap lembaga negara, yang dipandang tidak perlu dicantumkan secara terpisah antara lembaga penasehat dengan lembaga yang kemudian dinasehatinya dalam UUD 1945, seperti Dewan Pertimbangan Agung. Sebelum dihapus dalam UUD 1945, DPA diatur di Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung, tepatnya dalam ketentuan Pasal 16, yang di dalamnya terdiri dari 2 ayat UUD 1945 sebelum perubahan, bunyinya yaitu sebagai berikut.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
274
1. 2.
Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atau pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah (kursif penulis).
Kemudian terkait dengan Dewan Pertimbangan Agung, dalam Penjelasan Pasal 16 UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan, bahwa. Dewan ini ialah sebuah Council of State yang berwajib memberi pertimbanganpertimbangan kepada pemerintah. Ia sebuah badan penasehat belaka (kursif penulis). Kemudian setelah adanya amandemen terhadap ketentuan Pasal 16 UUD 1945 yang lama, maka dalam UUD 1945 berkaitan dengan ketentuan Pasal 16, ternyata kemudian hanya terdiri dari satu ketentuan, tanpa disertai dengan ayat sebagaimana dulunya. Hal ini dapat dilihat kembali dari ketentuan Pasal 16 UUD 1945 setelah diamandemen yang bunyinya, yaitu sebagai berikut Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (kursif penulis) Perubahan tersebut menunjukan bahwa keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperlukan, tetapi statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dihapusnya Dewan Pertimbangan Agung dari struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan keputusan yang dapat dipandang tepat untuk dilakukan. Dikarenakan suatu dewan yang sesungguhnya bertugas sebagai penasehat Presiden, ternyata secara struktur merupakan sebuah lembaga negara yang kedudukannya terpisah dan sejajar dengan lembaga negara yang kemudian diberi nasihat, yaitu lembaga kepresidenan. Dulunya Dewan Pertimbangan Agung hanya bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dan Wajib memberikan jawaban terhadap pertanyaan Presiden yang diberikan kepadanya (Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1967), namun terkait dengan diterima atau tidaknya pertimbangan yang sebelumnya diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung semuanya tergantung dari kehendak Presiden. Hal mana memang dikarenakan Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah badan yang tugasnya hanya sebagai penasehat belaka. Usul pertimbangan yang diberikan oleh DPA kepada
I Gusti Ngurah Santika, SPd
275
Presiden, baik diminta maupun tidak diminta, oleh karena sebelum dihapusnya DPA memiliki hak juga untuk mengajukan usul berupa pertimbangan kepada pemerintah. Selain itu, jika Presiden memerlukan pertimbangan dari DPA, maka Presiden dapat mengajukannya berupa pertanyaan tentang persolan yang dihadapinya, dan merupakan kewajiban pula dari DPA untuk kemudian menjawabnya, dan tentunya jawaban DPA tidaklah mengikat Presiden secara yuridis. Jelaslah, bahwa sebenarnya lebih efisien dan efektif jika sebuah badan penasehat Presiden, tidaklah terpisah dan berdiri sendiri secara sturutktural sebagai sebuah lembaga negara yang merdeka dan independen, apalagi memiliki kedudukan sejajar, yang notabene hanya merupakan organ pendukung daripada tugas-tugas Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan, dalam sejarah perjalanannya lembaga ini, pada era Soeharto hanya dijadikan tempat untuk menampung orang-orang yang dipandang dekat dengannya, pastinya dengan tujuan utamanya adalah agar mendapat posisi di pemerintah, termasuk orang yang kemudian dipandang tidak produktif. Bahkan, ada yang kemudian mengatakan bahwa DPA bukanlah dari singkatan Dewan Pertimbangan Agung, melainkan Dewan Pensiunan Agung. Memang pada era Orde Baru telah ditentukan keanggotaan DPA yang seharusnya terdiri dari unsur-unsur, seperti tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh karya, tokoh-tokoh daerah, dan tokoh-tokoh nasional (Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1967), dengan jumlah paling banyak 27 anggota, itupun sudah termasuk pimpinan. Namun, nyatanya rekruitmen anggota DPA hanyalah sekedar formalitas belaka, tidak lain dikarenakan yang kemudian menjadi anggotanya, hanyalah terdiri dari orang-orang kepercayaannya, bahkan bisa dikatakan dekat dengan pemerintah. Menurut penulis, pertimbangan itulah yang kemudian menjadi dasar untuk perlunya DPA itu dihapus dari struktur ketatanegaraan, sehingga sekarang ini berkaitan dengan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden, telah pula dibentuk sebuah Dewan Pertimbangan Presiden. Dengan demikian, Watimpres tidaklah merupakan sebuah lembaga negara yang berada di luar struktural pemerintah, melainkan lembaga yang kedudukan secara struktural merupakan bagian daripada pemerintah. Bahkan terkait dengan kedudukan DPA adalah badan yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden (Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2006). DPA memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dapatlah diberikan oleh perseorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan, baik diminta maupun tidak oleh Presiden (Lihat Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2006). Dan tentunya semua kekuatan mengikatnya pertimbangan yang kemudian diberikan oleh Watimpres tidaklah berbeda dengan DPA, sehingga semua pertimbangan yang diberikan badan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
276
tersebut adalah tergantung dari kehendak Presiden, apakah akan menerima pertimbangan tersebut ataukah tidak. Pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sekaligus dimaksudkan agar Presiden dalam mengambil setiap keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan cermat. Mengingat keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas orang-orang yang jujur, adil dan berkelakukan tidak tercela, negarawan, dan mempunyai keahlian di bidangnya, Presiden tentunya secara sungguh-sungguh memperhatikan nasihat dan pertimbangnnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dapat dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas permintaan Presiden dapat : mengikuti sidang kabinet; mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Anggota Watimpres diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian terkait dengan masa jabatan keaanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden adalah berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan Presiden atau mungkin berakhir dikarenakan diberhentikan sendiri oleh Presiden. Selain tugas-tugas seperti yang telah disebutkan di atas, Presiden ternyata juga memiliki tugas-tugas lainnya yang kemudian ditentukan dalam UUD 1945. Tugas lainnya tersebut merupakan tugas yang pada dasarnya memiliki hubungan dengan lembagalembaga negara lain, bahkan merupakan suatu keharusan dalam bentuk kerjasama antara Presiden dengan lembaga negara lainnya sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Seperti, hanyalah Presiden yang dapat mengajukan RUU APBN kepada DPR (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945), kemudian Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang sebelumnya telah mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (4) UUD 1945), meresmikan anggota BPK (23F ayat (1) UUD 1945), menetapkan hakim agung (Pasal 24A ayat (4) UUD 1945). Selain itu, Presiden berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) UUD 1945), menetapkan dan mengajukan 3 orang hakim konstitusi (Pasal 24 ayat (3) UUD 1945). Bebrapa tugas yang terakhir tersebut, merupakan fungsi dan wewenang daripada Presiden sebagai penyelenggara administrasi tertinggi menurut UUD 1945, yang bertugas untuk mengeluarkan keputusankeputusan berupa menetapkan pengangkatan, seperti anggota BPK, anggota hakim agung, dan tentunya 3 hakim MK.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
277
3.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, dalam kenyataannya DPR untuk sekarang merupakan sebuah lembaga negara hal mana telah mengalami perubahan sangat mendasar, yang kemudian dalam kesehariannya berkedudukan dan berfungsi sebagai lembaga legislatif. Sebelum membahas berkaitan dengan DPR sebagai lembaga legislatif di Indonesia, maka penulis kiranya terlebih dahulu akan memaparkan beberapa hal terkait dengan badan legislatif. Menurut Simbolon (2009;40) bahwa badan legislatif adalah lembaga legislate atau pembuat undang-undang. Kekuasaan legislatif diwujudkan dalam sebuah badan legislatif atau legislature, yang mencerminkan fungsi dari badan tersebut, yakni sebagai pembentuk undang-undang (legislate). Hutington (1983;167) berpendapat bahwa fungsi legislatif atau pembentuk undang-undang mempunyai lebih banyak kekuasaan dibandingkan dengan fungsi administratif atau pelaksana undang-undang. Undang-undanglah yang sebelumnya dibentuk oleh badan legislatif, kemudian menjadi pedoman utama bagi eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Juga tidak lain dikarenakan, bahwa undang-undang itu merupakan wujud daripada kehendak rakyat yang berdaulat. Dengan pendapat yang senada, Amal dan Panggabean (2012;171) menyatakan bahwa dalam teori maupun praktek demokrasi tradisional, lembaga legislatif memiliki posisi sentral. Pernyataan tersebut dapatlah kemudian dapatlah diverifikasi kebenaran dalam kenyataan, apalagi kemudian sebuah negara yang sebelumnya mengaku sebagai negara demokrasi, terutama dengan menempatkan kedudukan negara berada di bawah kedaulatan rakyat. Lembaga inilah merupakan simbol daripada ide kedaulatan rakyat, serta sebagai jaminan utama bahwa jalannya pemerintahan akan benar-benar tidak menyimpang, dari tujuan semula seperti apa yang sebelumnya memang dikehendaki rakyat. fungsi tersebut dilakukan dengan berbagai perlengkapan, yang memang bertugas untuk melakukan berbagai bentuk pengawasan yang melekat, karena telah diberikan secara konstitusional oleh konstitusi. Pengaturan dalam bentuk undang-undang oleh badan legislatif merupakan masalah yang kemudian menjadi perhatian utama dalam lintasan sejarah perkembangannya di negara-negara modern, terutama negara yang kemudian mengaku demokrasi sebagai landasan utama kehidupannya. Hal tersebut membuktikan bahwa lembaga legislatif memiliki kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting bahkan bisa dikatakan bahwa fungsi dan kewenangan yang dimilikinya menentukan kehidupan rakyat, terutama bagi negara-negara yang kemudian mengaku sebagai penganut demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut Strong (1966;233) menyatakan pentingnya fungsi legislatif dalam pemerintahan modern telah sangat meningkat seiring dengan pasang surut demokrasi. Proses perundang-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
278
undangan seperti yang dikenal sekarang sesungguhnya termasuk perkembangan baru. Dikarenakan pada awalnya terkait dengan kewenangan daripada pembentukan undangundang dalam lintasan sejarah, ternyata pernah dipegang oleh satu tangan, yaitu raja absolut, yang pada dasarnya memusatkan semua kekuasaan. Kemudian timbul kesadaran bahwa apabila kekuasaan dalam membentuk undang-undang diberikan kepada eksekutif, maka undang-undang yang dibentuknya akan berpotensi atau setidak-tidaknya cenderung sifatnya adalah menindas rakyat. Dengan kesadaran itulah, rakyat kemudian berangsurangsur mencoba untuk membatasi kekuasaan raja dalam bidang pembentukan undangundang, sampai akhirnya berhasil menghapus tugas tersebut dan menyelenggarakannya sendiri dengan membentuk sebuah badan, yang kemudian disebut dengan parlemen. Badan inilah yang selanjutnya bertugas untuk membuat kebijakan, yang sifatnya mengatur serta mengikat tidak hanya rakyat saja, namun juga mengikat negara termasuk para penyelenggara negara itu sendiri, yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi organ negara. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa tugas dari badan legislatif dalam membentuk undang-undang merupakan titik sentral, dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan seperti yang telah ditentukan oleh konstitusi. Bahkan, Soehino (1983;109) kemudian menyatakan bahwa kekuasaan perundang-undangan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam negara, sebab yang menyatakan kehendak daripada negara. Kekuasaan legislatif pada dasarnya merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dalam pada itu undang-undang dibentuk tersebut, dapatlah kemudian dikatagorikan sebagai bagian dari norma hukum yang memiliki sifat tersendiri dan berbeda dengan norma lainnya. Bahkan menurut Indrati (2007;30) norma hukum yang dibentuk tersebut merupakan norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (regeling), yaitu yang umum abstrak dan berlaku terus-menerus. Tentunya akan sangat berbeda dengan norma hukum yang bersifat menetapkan (beschikking), yaitu individualkongkret dan berlaku sekali selesai. Undang-undang yang dibentuk kemudian oleh lembaga legislatif sebagai pedoman utama bagi eksekutif dan yudikatif, dalam menjalankan tugastugasnya untuk melaksanakan serta menegakan aturan tersebut, apabila dalam kenyataannya ada tindakan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun warga negara, ternyata melanggar undang-undang yang sebelumnya telah ditetapkan oleh rakyat sendiri melalui wakilnya di lembaga parlemen. Berkaitan dengan istilah legislatif, terdapat beberapa peristilahan lain untuk menyebut badan ini, khususnya berkait dengan fungsinya. Badan legislatif sering disebut sebagai
I Gusti Ngurah Santika, SPd
279
assembly, peristilahan ini menekankan pada unsur berkumpul untuk membicarakan permasalahan publik. Di sejumlah negara dikenal dengan nama parliament, yang menekankan pada unsur bicara (parle) dan merundingkan. Dan dapat diartikan suatu tempat atau badan di mana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk memperbincangkan hal-hal yang penting bagi rakyat (Prodjodikoro,1981;28). Sedangkan di Indonesia, istilah badan ini dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Peoples Representative Body), di mana unsur keterwakilan/representasi dari anggota-anggotanya adalah sesuatu yang utama. Menurut Asshiddiqie (2010;12) bahwa lembaga perwakilan rakyat atau kemudian disebut parlemen, yang berasal dari perkataan le parle yang berarti to speak dalam rangka menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat yang berdaulat itu. Bahkan, badan inilah yang mencerminkan daripada kehendak rakyat, yang akhirnya kehendak rakyat tersebut, kemudian direalisasikan oleh DPR menjadi sebuah kebijakan dalam bentuk undangundang, yang tentunya sifatnya mengatur, mengikat negara, sehingga pada akhirnya bertujuan untuk dapat melindungi rakyat sendiri dari ancaman penguasa. Lembaga legislatif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi negaranegara yang dapat dikatakan modern, dengan wujudnya yang mengutamakan sistem perwakilan sebagai bentuknya. Dikarenakan untuk sekarang, tidaklah mungkin melaksanakan pemerintahan secara langsung, sebagaimana dahulu di Yunani, yang menggunakan model sistem demokrasi langsung, dengan mengikutkan seluruh partisipasi dari rakyat dalam mengelola pemerintahan. Bahkan, konsep demokrasi itu sendiri sebenarnya berasal dari Yunani, pernyataan tersebut adalah sesuai dengan apa yang kemudian dikemukakan oleh Dahl (2001) bahwa orang Yunani itulah, mungkin sekali orang Athena, yang menciptakan istilah demokrasi, atau demokratia, dari kata-kata Yunani demos, rakyat, dan kratos, pemerintahan. Demokrasi yang pertama itu adalah demokrasi langsung yang kecil ruang-lingkupnya, berbentuk demokrasi langsung, dengan pengertian tidak mengenal demokrasi perwakilan. Terdapat kesan bahwa menurut pandangan orangorang Athena itu, demokrasi perwakilan itu bukanlah demokrasi sama sekali, karena dalam demokrasi perwakilan orang tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban kedaulatannya dengan cara yang langsung, akan tetapi menyerahkannya kepada orang lain. Dengan demikian, seakan-akan ia telah menyerahkan hak kedaulatannya itu kepada orang lain (Zainuddin dalam Dahl,1992;xxix). Keterlibatan rakyat secara langsung sebagaimana yang terjadi pada zaman Yunani, pastinya tidak mungkin dapat dipraktikan kembali dalam negara modern seperti sekarang. Dengan berbagai pertimbangan, demokrasi langsung memang tidak mungkin dilakukan, dikarenakan untuk sekarang ini tidaklah adanya tempat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
280
yang mampu serta dapat menampung seluruh warga negara yang begitu banyak jumlahnya. Bahkan, dapatlah kemudian dibayangkan terkait dengan perkembangan negara modern seperti sekarang ini, yang disertai jumlah penduduk begitu banyaknya, jika dilakukan dalam bentuk musyawarah tentunya akan sulit sekali untuk dilaksanakan, apalagi menyediakan tempat untuk melaksanakan musyawarah sebagaimana dimaksudkan di atas. Selain itu, dalam pengambilan keputusan akan mengalami suatu kesulitan apalagi untuk tercapainya suatu mufakat, karena sulit sekali untuk mengambil suara daripada warga yang hadir. Ditambah kompleksnya tugas-tugas daripada negara modern, sehingga pastinya memerlukan orang-orang yang memang secara khusus berkecimpung untuk itu, serta memiliki keahlian dibidang kenegaraan yang dibutuhkan. Namun, tentunya tidaklah bertujuan negatif, dengan bermaksud mengurangi daripada makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. oleh karena itu, suatu keniscayaan untuk selalu ikut serta melibatkan partisipasi rakyat dalam pengelolan negara, yaitu dengan jalan membentuk sebuah badan, yang dalam menjalankan kebijakannya harus selalu berpedoman bahkan mengatasnamakan rakyat yang diwakilinya. Menurut John Locke, walaupun kekuasaan telah diserahkan kepada suatu organ yaitu negara, namun rakyat sebagai suatu kesatuan politik masih dapat menyampaikan tuntutan-tuntutan dan meminta perhatian terhadap pelanggaran yang terjadi (Safaat,2011;42). Dengan demikian, pada dasarnya rakyat tetap sebagai pemegang kedaulatan dalam suatu negara, hanya saja kedaulatan rakyat tersebut kemudian diwakilkan kepada sebuah badan. Pengertian kedaulatan sebagaimana dimaksud di atas, bukanlah semata-mata pengertian daripada kedaulatan (sovereigniteit) menurut Jean Bodin yang menurutnya adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum dalam suatu negara, yang sifatnya tunggal, asli, dan abadi (Astawa dan Suprin,2009;108). Karena telah ditentukan bahwa selain badan legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang, ternyata ada juga badan lainnya yang bertugas untuk ikut terlibat secara langsung dalam pembentukan undang-undang, seperti eksekutif ( khususnya Indonesia). Hanya saja kemudian disadari, bahwa kekuasaan membentuk undang-undang tetaplah harus berada pada tangan legislatif sebagai lembaga utama dalam sistem perwakilan negara modern, bukannya berada pada badan lainnya. Tidak lain, dikarenakan pada awalnya memang hanya badan inilah yang memang diserahi oleh rakyat untuk mengatur mereka, melalui keputusankeputusannya yang berbentuk undang-undang, yang tentunya undang-undang tersebut bersifat mengikat bahkan memaksa untuk kemudian dilaksanakan. Dikarenakan badan perwakilan tersebut sebagai perpanjangan tangan rakyat, dengan demikian kedaulatan dalam arti sebenarnya, tetaplah terletak di tangan rakyat sebagai sebuah negara demokrasi. Untuk mengetahui hal itu, maka dianggap perlu untuk menyertakan wakil-wakil dari
I Gusti Ngurah Santika, SPd
281
segenap lapisan masyarakat di dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum (Soekanto,2009;215). Dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya tersebut, pada dasarnya terlihat bahwa badan ini merupakan representasi utama dari rakyat yang sebetulnya berdaulat. Walaupun kenyataannya dalam pengambilan keputusan-keputusan tidaklah pernah mengikutkan rakyat secara langsung, karena memang hal tersebut tidaklah dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan, namun demikian rakyat pada dasarnya tetap pemilik kedaulatan yang utuh dan hakiki. Sehingga kemudian Soemantri (1992;10) berpendapat bahwa demokrasi dalam arti formal telah mengalami suatu perkembangan, yaitu dari demokrasi langsung, sebagaimana pernah dilaksanakan dalam negara-kota (city state) di Yunani Kuno, menjadi demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung juga dinamakan demokrasi perwakilan, yaitu demokrasi yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga/badan perwakilan rakyat. Dengan demikian, lembaga politik demokrasi Yunani itu, walaupun merupakan suatu inovasi baru di masa mereka itu, benarbenar telah di kesampingkan, malah juga ditolak sama sekali dalam perkembangan demokrasi perwakilan modern (Dahl,2001;17). Untuk Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, untuk badan legislatif ternyata dikenal kemudian dengan adanya dua badan perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah. Kedua dewan tersebut sama-sama menjalankan fungsi parlemen, hanya saja pembedaannya kemudian bahwa DPD memiliki suatu fungsi tunggal, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan daerah secara keseluruhan yang terlepas dari kepentingan individu, sedangkan untuk DPR berfungsi memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk lembaga DPR yang merupakan simbol daripada rakyat berdaulat, bahkan terbentuknya memerlukan pratisipasi langsung daripada rakyat, khususnya dalam pemilu untuk memberikan suaranya. Tugas utama yang mungkin diembannya adalah harus selaras dengan kehendak rakyat, untuk kemudian memperjuangkan hak-haknya di hadapan penguasa. Pastilah terbentuknya DPR tidak atas dasar cita-cita demokrasi yang mempunyai semangat egaliter (Sulardi,2009;13). Dibentuknya DPR merupakan implementasi dari Indonesia yang mengaku sebagai negara demokrasi, dengan cara menempatkan wakil-wakil rakyat, yang untuk selanjutnya akan memperjuangkan aspirasinya. Tentunya aspirasi tersebut, kemudian direalisasikan dalam suatu bentuk kebijakan yang bersifat mengatur, mengikat dan bahkan memaksa, baik rakyat maupun penyelenggara negara, seperti dalam bentuk undang-undang. Dengan begitu, DPR merupakan sebuah forum yang bertugas untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Sehingga dengan demikian, apa yang kemudian menjadi aspirasi rakyat hendaknya perlu didengar
I Gusti Ngurah Santika, SPd
282
kembali oleh wakil rakyat, untuk diperjuangkan di forum tersebut sampai pada akhirnya mampu terwujud, seperti apa yang memang diinginkan rakyat . Karena pada dasarnya dalam negara demokrasi, rakyat harus tetap ikut terlibat dalam mengambil suatu keputusan, walaupun secara tidak langsung, kerena hanya melalui wakil-wakilnya, sehingga demokrasi yang dijalankan oleh negara tersebut adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi dalam arti sistem pengambilan keputusan di mana semua anggota atau penduduk memainkan peranan aktif dalam proses yang terus menerus adalah tidak mungkin (Marti,1984;Lvi). Demokrasi yang demikian itu, kemudian mempunyai konsekuensi-konsekuensi: 1. Keharusan adanya lembaga perwakilan rakyat. 2. Keharusan adanya seleksi, baik melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia maupun cara lain. 3. keharusan adanya partai politik. 4. keharusan adanya lembaga yang mempunyai tugas pelaksanaan, dan yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui badan perwakilan rakyat (Seomantri,1992;18). Apa yang telah dijelaskan seperti tersebut di atas, merupakan awal mula kelahiran daripada sebuah badan perwakilan rakyat, seperti halnya DPR. Hal ini tentunya akan berbeda dengan latar belakang lahirnya DPD, Kelahiran DPD memang tak lepas dari upaya penguatan otonomi daerah (local autonomy), yang selama pemerintahan Orde Baru berkuasa tidak diperhatikan, sebagai imbas dari model pemerintahan sentralistis. Pembedaan hakikat perwakilan ini penting dilakukan, untuk menghindari adanya pengertian keterwakilan ganda (double representative). Tentunya, DPD dan DPR masingmasing memiliki tugas yang berbeda, terutama dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dikarenakan pada hekikatnya mereka membawa visi dan misi yang berbeda serta memperjuangkan kepentingan yang berbeda pula. Tetapi perlulah dipikirkan kembali, bahwa pada dasarnya daerah tidak lain merupakan bagian daripada wilayah Indonesia. Jadi, mau atau tidak mau kemudian, kita tidaklah dapat melepaskan pengertian perwakilan hanya dari segi sistem pemilihan yang berbeda terkait dengan kedua badan tersebut, ataupun hanya dari nama yang diberikan kepada badan tersebut. Namun, dapat dikemukakan dengan kesadaran bahwa untuk ke depannya daerah perlu untuk diperhitungkan kembali, terutama dalam membuat suatu kebijakan negara, karena daerah sebagai dari bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memulai pembahasan terhadap DPR, maka terlebih dahulu akan dibahas pasalperpasal agar dapat lebih dipahami tentang adanya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Seraya untuk membandingkan dengan ketentuan DPR, sebelum
I Gusti Ngurah Santika, SPd
283
maupun sesudah diadakan amandemen terhadap UUD 1945, khususnya berkaitan dengan tugas dan wewenang DPR. Legitimasi DPR berkaitan dengan kedudukannya setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, adalah jauh lebih kuat apabila dibandingkan dengan sebelum perubahan terhadap UUD 1945. Di mana untuk pengisian keanggotaan di DPR, maksudnya anggotaanggota yang akan duduk di dalamnya merupakan orang dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemilihan umum yang sifatnya langsung umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (Pasal 22E ayat (1) UUD 1945). Dalam Penjelasan UU No 8 Tahun 2012 diberikan pengertian mengenai asas-asas dalam pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun (kursif penulis). Lebih lanjut untuk sekarang ini telah ditentukan pula bahwa orang-orang yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, adalah orang-orang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, sistem pemilihan terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat telah melibatkan pratisipasi rakyat secara langsung, hal mana adalah sangatlah berbeda seperti apa yang pernah diterapkan pada waktu Orde Baru, ketika itu banyak anggota DPR yang kemudian diangkat oleh Presiden. Sehingga dengan dasar pemikiran tersebut di ataslah, maka untuk sekarang semua anggota DPR dipilih melalui pemilu. Hal ini dapat diketahui kemudian dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, yang bunyinya menyatakan bahwa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum (kursif penulis).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
284
Pengaturan konstitusional ini sangatlah berbeda dengan ketentuan sebelumnya, terutama ketika UUD 1945 belumlah diamandemen, khususnya terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum diamandemen, yang pada dasarnya ditentukan untuk mengatur kembali terkait dengan tata cara ataupun prosedur pengisian keanggotaan DPR. Dalam pada itu, ketentuan tersebut kemudian menentukan bahwa tentang pengaturan tatacara untuk mengisi keanggotaannya, ditentukan kembali dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, UUD 1945 tidaklah menentukan dengan jelas apakah anggota yang nantinya akan duduk di DPR dipilih melalui pemilihan umum ataukah tidak. Hal mana semua itu adalah sangat tergantung daripada undang-undang yang nantinya akan mengaturnya kembali. Oleh karena itu, Presiden dan DPR sebagai badan yang memang telah ditentukan oleh UUD 1945, untuk bertugas dalam membuat undang-undang, yang selanjutnya akan menentukan kemudian apakah dalam undang-undang, terkait dengan keanggotaan DPR, akan dipilih oleh rakyat secara langsung ataukah diangkat oleh Presiden. Selengkapnya dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, yang berbunyi. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang (kursif penulis). Aturan yang sama juga dapat ditemukan kembali dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 sebelum diamandemen, yang pada dasarnya hanya menyerahkan pengaturan mengenai susunan Dewan Perwakilan kepada undang-undang. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 sebelum diamandemen berbunyi. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang (kursif penulis). Dalam sejarahnya adanya ketentuan tersebut di atas, telah disalahgunakan oleh penguasa, dalam rangka semakin memperkuat dan memperkokoh kedudukannya. Di mana Presiden sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, telah ditentukan merupakan lembaga pemegang kekuasaan eksekutif, namun sekaligus juga secara tidak langsung sebagai ketua legislatif. Dengan kekuasaan yang besar dalam bidang pembentukan undangundang, Presiden selalu saja mendominasi setiap pembentukan undang-undang, termasuk undang-undang yang mengatur lembaga DPR, terutama dalam hal tata cara pengisian keanggotaannya. Bahkan, untuk semakin melegitimasi dan memperkokoh daripada kedudukan Presiden, maka untuk keanggotaan DPR ternyata banyak yang kemudian diangkat/ditunjuk oleh Presiden, untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah. Terjadinya peristiwa sejarah tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan pengertian negara
I Gusti Ngurah Santika, SPd
285
demokrasi, terutama yang menganut konsep sistem perwakilan sebagai bentuk utamanya. Adanya pengangkatan terhadap anggota DPR yang merupakan wakil rakyat, adalah bentuk pelanggaran yang sifatnya nyata terutama terhadap asas negara demokrasi dengan mengutamakan sistem perwakilan, di mana seharusnya wakil-wakil rakyat seharusnya dipilih dan ditentukan kemudian melalui pemilihan umum. Padahal terlihat jelas sekali bahwa tahapan ataupun mekanisme pemilihan anggota yang duduk di DPR, sebagai lembaga perwakilan tidaklah mencerminkan mekanisme demokrasi yang benar. Apalagi agar DPR dapat memberikan suatu pertanggungjawaban, terutama kepada rakyat sebagai pemegang kadaulatan dalam arti yang sesungguhnya. Padahal pemilu yang terselenggara seharusnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan, serta makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Bahkan, berkaitan dengan hal tersebut di atas, Asshiddiqie, (2010;104) menyatakan bahwa prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat itu juga tercermin dalam keseluruhan mekanisme dan prosedur-prosedur yang diatur dalam UUD 1945, seperti prosedur rekruitmen politik, mekanisme penyusunan kebijakan atau fungsi legislasi, prosedur pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kekuasaan, dan sebagainya. Dengan demikian, prosedur yang dianut oleh UUD 1945 sebelum diamandemen, dalam menentukan susunan maupun tata cara rekruitmen keanggotaan DPR, telah disalahgunakan oleh Presiden, dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kekuasaan begitu besar yang dimiliki Presiden, untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pengisian keanggotaan DPR dengan undang-undang yang dibuat bersama DPR. Disatu pihak terlihat sekali bahwa sebelum adanya perubahan terhadap UUD 1945, DPR sebagai wakil rakyat ternyata tidak mampu untuk berbuat banyak, terutama dalam menghadapi besarnya kekuasaan eksekutif. Hal tersebut bisa terjadi, dikarenakan rekruitmen politik keanggotaan DPR saja, sudah dapat dipastikan bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang tentunya akan berimbas pula kepada fungsi yang dimiliki oleh lembaga ini, baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan yang sebelumnya telah diamanatkan oleh UUD 1945. Namun, dengan kelemahan yang dimiliki oleh UUD 1945 sebelum perubahan, dikarenakan terlalu banyak mengatribusikan pengaturan selanjutnya dalam bentuk undang-undang, sedangkan dilain pihak Presiden sangatlah dominan dalam pembentukan undang-undang, menyebabkan Presiden kemudian membentuk undang-undang, dengan mendeskriditkan kedudukan lembaga DPR. Padahal
I Gusti Ngurah Santika, SPd
286
seharusnya dalam suatu negara demokrasi, yang sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari suatu masyarakat politik ikut serta atas dasar perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu, ternyata tidaklah terjadi di Indonesia. Ternyata pengertian sebagaimana di atas, jika dibaca dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, terutama hubungan antara Presiden dan DPR, hal mana sepertinya terlihat bahwa DPR dalam kenyataannya yang bertanggungjawab kepada Presiden, bukan sebaliknya di mana seharusnya DPR yang kemudian mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Dengan demikian, besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden, kemudian ditambah dengan memanfaatkan berbagai kelemahan-kelemahan yang melekat pada UUD 1945, baik dalam distribusi kekuasaan maupun dalam pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang, telah menyebabkan Presiden merekayasa demokrasi, dengan menjadikan DPR sebagai tukang stempel Orde Baru. Namun, untuk sekarang ini, secara konstitusional berkaitan dengan keanggotaan DPR, semuanya merupakan hasil dari pemilihan umum, sehingga tidak akan ada lagi anggota DPR yang kemudian diangkat oleh Presiden, seperti di masa lalu. Untuk sekarang, berkaitan dengan tata cara rekruitmen anggota DPR telah ditetapkan pula dalam UUD 1945, yaitu dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hanya melalui pemilihan umumlah, kemudian seseorang dapat duduk menjadi anggota DPR, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yang bunyinya. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kursif penulis). Bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, selain itu, pemilihan umum adalah sebagai sarana perwujudan daripada kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, persyaratan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, untuk kemudian dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pesertanya atau calonnya haruslah merupakan anggota dari partai politik (lihat ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945). Partai politik merupakan suatu organisasi politik yang bertugas untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan cara menyodorkan tokoh-tokoh politiknya yang dianggap mampu untuk mengikuti kompetisi dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat kemudian dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
287
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik (kursif penulis). Prinsip yang sama dapat kita temui kembali dalam ketentuan Pasal 67 UU No. 27 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa : DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum (kursif penulis). Berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditemui kembali dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang di dalamnya menyatakan bahwa : Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik (kursif penulis). Kemudian dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tepatnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa Partai Politik melakukan rekruitmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. dst(kursif penulis). Oleh karena itu, dapatlah kemudian dikatakan bahwa partai politik memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam menyeleksi pemimpin negara (political recruitmen), namun terkait dengan persetujuan terhadap keputusan partai politik tersebut, adalah tetap berada di tangan rakyat yang kemudian dilaksanakan melalui pemilu. Dengan demikian, orang yang ingin menjadi anggota DPR, adalah orang-orang yang pilihan, tentunya akan memiliki kualitas dan integritas untuk mewakili rakyat dalam memperjuangkan kepentingannya. Setidaknya pernyataan tersebut perlulah didasari, bahwa calon yang diusulkan oleh partai politik merupakan suatu tokoh yang tidak hanya popular namun memiliki kredibilitas dan integritas. Kemudian pengujian terhadap kedua syarat tersebut di atas, akan dilanjutkan kembali dalam pemilihan umum sebagai bagian daripada ujian terhadap kapabilitas dan kredibilitas calon wakil rakyat dimata rakyat sendiri, yang calon wakil rakyat tersebut sebelumnya diusulkan partai politik. Selanjutnya, menurut Santoso dan Supriyanto (2004) bahwa baik pemilu pertama di era Soekarno tahun 1955, pemilu-pemilu dimasa Soeharto (1971-1997), maupun pemilu pertama pasca Soeharto tahun 1999 kesemuanya dilandasi oleh UUD 1945 yang ternyata tidak menyebutkan kata pemilu. Hal mana dapatlah kemudian dilihat kembali dengan menelusuri sejarah ke belakang, terutama pada saat penyusunan UUD 1945, dimana pada
I Gusti Ngurah Santika, SPd
288
saat itu diwarnai oleh situasi dan keadaan yang diliputi perang. Sehingga para penyusun UUD 1945 tidak punya banyak waktu untuk memikirkan dan bahkan berkehendak untuk melaksanakan pemilu, apalagi akan membuat pengaturan tentang pemilu yang terperinci dalam UUD 1945. Tidak adanya pencantuman terkait pengaturan pemilu, merupakan suatu pengaturan yang selaras dengan tidak dicantumkannya pula tentang partai politik dalam UUD 1945, yang jika dilihat dari sudut demokrasi, sebenar partai politik merupakan salah satu pilar utama negara demokratis, karena merupakan sebagai peserta utama dalam pemilu. Hal pertama yang paling penting untuk diperhitungkan pada waktu itu oleh para pemimpin bangsa, adalah kemerdekaan secepatnya. Karena tidaklah mungkin dapat menyelenggarakan pemilu ataupun kegiatan yang ada hubungan dengan kehidupan demokrasi dalam keadaan terjajah. Tidak lain tujuan utama pada waktu itu, adalah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diperoleh. Walaupun nanti dalam perjalanannya melawan penjajah, yang ingin mencoba kembali untuk menancapkan kuku imperialismenya di tanah air, dengan menuduh Indonesia sebagai negara yang tidaklah bersifat demokratis, dikarenakan ketiadaan daripada pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, pemilu dan badan legislatif. Bahkan berbagai upaya telah dilakukan oleh penjajah, dengan merongrong negara yang baru merdeka ini, yaitu mempropagandakan kepada dunia internasional, bahwa negara ini bukanlah negara yang bersifat demokratis. Peristiwa itulah kemudian yang memaksa para pendiri bangsa, untuk membentuk struktur demokrasi dengan tujuan agar terhindar dari dugaan-dugaan dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak demokratis. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya pemerintah berjanji akan melaksanakan pemilu pada Januari 1946, sehingga pada waktu itu masyarakat sendiri diberikan kesempatan, untuk mendirikan partai politik berdasarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Walaupun kebebasan untuk mendirikan partai politik, yang merupakan tiang dari demokrasi tersebut, tidaklah dapat dilakukan sebebasbebasnya, karena masih adanya pembatasan mulia bahwa partai politik yang didirikan tujuannya adalah semata-mata hanya untuk mendukung pemerintah, dalam rangka memperkuat perjuangan, terutama ikut serta untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Itulah kiranya kemudian yang menjadi latar belakang menurut penulis, mengapa di dalam UUD 1945 dalam kenyataannya tidak disebutkan kata pemilu maupun partai politik. Namun, karena sebagai sebuah negara yang mengaku demokratis, para pemimpin bangsa sangat sadar bahwa diperlukan sebuah mekanisme pemilihan wakil-wakil rakyat, yang ditentukan untuk dipilih melalui pemilu dengan prinsip jujur dan adil. Bahkan, pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1955, dimana pada saat itu memilih anggota lembaga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
289
perwakilan rakyat, yaitu DPR dan Konstituante. Pemilu tersebut merupakan pemilu pertama, yang diakui dan bahkan mendapatkan pujian dari dunia internasional sebagai pemilu yang sangat demokratis. Namun, untuk sekarang setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945, berkaitan dengan adanya pemilihan terhadap anggota DPR telah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945, bahwa anggota DPR haruslah dipilih oleh rakyat secara langsung. Untuk terselenggaranya pemilu, maka diperlukan infrastruktur demokrasi yang dalam hal ini adalah partai politik. Setelah reformasi, partai politik memiliki peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan menentukan kehidupan serta kadar dari demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Masalah utama yang mendapatkan sorotan adalah menyangkut tata cara pengisian keanggotaan lembaga negara, yang harus dicalonkan melalui partai politik. Bahkan, untuk anggota DPR partai politik sangat dominan dalam menentukan, misalnya dalam pemberhentian antar waktu, hal mana tentunya berkaitan erat dengan diberhentikannya atau tidak dari keanggotaan DPR, karena misalnya diusulkan oleh partai politiknya, tetapi tentunya dalam mengusulkan pemberhentian anggota DPR oleh partai politik tersebut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, alasan lainnya, yaitu karena anggota DPR yang diberhentikan telah menjadi anggota partai politik lain (lihat ketentuan Pasal 213 UU No. 27 Tahun 2009). Kemudian keterangan yang sama dapat juga ditemukan dalam kaitannya, jika seseorang menjadi partai politik lain atau ikut partai politik baru, maka keanggotaan dari partai politik yang sebelumnya akan diberhentikan pula, kemudian apabila orang yang diberhentikan dari partai politik yang lama, namun dia mewakili partai politik lama tersebut sebagai anggota DPR, tentunya pemberhentian dari keanggotaan partai politiknya tersebut, juga akan diikuti pula dengan adanya pemberhentian dalam keanggotaannya sebagai anggota DPR (lihat ketentuan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2008). Selain pemberhentian seperti tersebut di atas, ternyata partai politik juga memiliki hak untuk menggantikan anggotanya yang duduk di DPR antar waktu, biasanya disebut dengan hak recall. Salah satu alasan penggantian antar waktu dalam ketentuan Pasal 213 huruf c adalah diberhentikan, diberhentikannya antar waktu yang berkaitan dengan partai politik apabila memenuhi syarat, seperti diusulkan oleh partai politiknya, tentunya dalam mengusulkan pemberhentian antar waktu dari keanggotaan DPR, oleh partai politik yang bersangkutan tersebut, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian juga dikarenakan yang bersangkutan (yang di recall) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau menjadi anggota partai politik lain (lihat Pasal 213 ayat (2) huruf e,h, i).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
290
Sistem pemilihan umum yang digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah dengan sistem proporsional yang bersifat terbuka, tentunya akan berbeda pula dengan pemilihan umum yang bersistem distrik, seperti pemilihan anggota DPD. Bahkan ketentuan ini sudah ditentukan dengan jelas dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah. Ketentuan tentang sistem pemilihan umum untuk anggota DPR, dapat ditemukan pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 2012, khususnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (1), yang bunyinya. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD. kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka (kursif penulis). Yang berarti untuk terpilihnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus terlebih dahulu mendapat jumlah suara tertentu, seperti yang dipersyaratkan dalam undangundang. Sehingga, untuk menjadi seorang wakil rakyat yang duduk di DPR, setidaknya harus dipersyaratkan untuk memiliki dukungan rakyat, khususnya dalam pemilu. Sistem pemilu proporsional dapat memberikan kesempatan kepada suara rakyat betapapun kecil manfaatnya, untuk menempatkan calonnya di dalam lembaga perwakilan. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa dalam sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional, untuk memilih anggota legislatif akan lebih menjamin prinsip keterwakilan, dalam lembaga perwakilan. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, berarti setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pemilihan umum proporsional, maka berikut ini merupakan tabel yang berkaitan dengan pemilihan umum proporsional, terutama tentang kelebihan dan keuntungannya. Keuntungan Sistem Proporsional Kelemahan Sistem Proporsional 1. Sistem proporsional lebih representatif, 1. Sistem ini kurang mendorong partaikarena jumlah kursi partai dalam partai partai untuk berintegrasi atau parlemen sesuai dengan jumlah suara bekerjasama satu sama lain dan masyarakat yang diperoleh dalam memanfaatkan persamaan-persamaan pemilihan umum. yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah partai politik. 2. Sistem proporsional dianggap lebih 2. Sistem ini mempermudah fragmentasi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
291
demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang atau wanted. Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun, memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen. Rasa keadilan (sense of justice) masyarakat sedikit banyak terpenuhi.
partai. Jika timbul konflik dalam partai, anggota cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilihan umum. Jadi, kurang menggalang kekompakan dalam tubuh partai.
3. Sistem proporsional memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai melalui Sistem Daftar, karena pimpinan partai menentukan daftar calon. 4. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar (bisa sebesar provinsi), sehingga sukar untuk dikenal orang banyak. Kedua, karena peran partai dalam meraih kemenangan lebih besar ketimbang kepribadian. Dengan demikian, si wakil akan lebih terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah umum kepentingan distrik serta warganya. 5. Karena banyaknya partai partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50 + satu) dalam parlemen, yang diperlukan untuk pemerintahan. Partai yang terbesar terpaksa dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas. Koalisi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
292
semacam inijika diselenggarakan dalam sistem parlementersering tidak lama umurnya, dan hal ini tidak membina stabilitas politik. Dalam sistem presidensial perubahan dalam komposisi di parlemen tidak terlalu mempengaruhi masa jabatan eksekutif. Di Amerika bisa saja Congress mengalami perubahan dalam komposisinya, sehingga misalnya badan itu dikuasai oleh Partai Demokrat, tetapi presiden serta kabinetnya tetap bertahan selama empat tahun. Diolah dari Budiardjo (2008) Berbeda pada saat Orde Baru berkuasa, hal mana kemudian hanya yang mendapatkan nomor urut terataslah, dapat dipastikan menjadi pemenang atau sering disebut dengan nomor urut jadi. Dengan demikian, jika nomor urut pertama telah memenuhi suara untuk mendapatkan kursi di DPR, maka kalau kemudian ternyata ada sisa suara untuk mendapatkan kursi lagi, maka barulah nomor berikutnya yang akan mendapatkan kesempatan untuk duduk sebagai anggota DPR, dan begitulah seterusnya. Dengan sistem tersebut kedudukan partai politik/elit/pimpinan politiklah, yang lebih dominan untuk mempertimbangan sampai dengan menentukan calon-calon mana, yang kemudian ditempatkan pada daftar peserta pemilu dengan nomor urut tertentu. Ketentuan tersebut merupakan ciri daripada sistem pemilu proporsional dengan stelsel daftar tertutup, dikarenakan suara hanya diberikan pada partai politik, bukan kepada calon. Sedangkan untuk pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka, rakyat benar-benar langsung berdaulat untuk menentukan siapakah nantinya yang akan duduk menjadi wakilnya di DPR, untuk selanjutnya memperjuangkan aspirasinya dalam berhadapan dengan pemerintah. Karena pencalonannya dari partai politik, tentunya partai politik memiliki peran yang tidak kecil, khususnya untuk memperhatikan kualitas calon-calonnya, agar dikemudian hari jika nantinya mereka terpilih, akan benar-benar mampu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Tetapi jika partai politik, merekruitmen orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas dan integritas untuk menjadi konstestan, maka rakyat akan memberikan penilain yang buruk, yaitu dengan cara tidak akan memilih calon dari partai politik tersebut pada saat pemilu. Resiko besar akan ditanggung diperoleh partai politik kelak, yang menyodorkan calon wakil rakyat, tetapi tidak sesuai dengan kehendak rakyat adalah tidak terpilihnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
293
calon yang sebelumnya diusung oleh partai politik tersebut, hal mana juga tentunya akan berimbas pula, terhadap perolehan kursi dari partai politik tersebut di lembaga perwakilan. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka dapat menyeimbangkan peran parpol untuk menyeleksi kader-kadernya dan peran rakyat pemilih untuk menentukan sendiri wakilwakil yang akan duduk di legislatif sesuai dengan yang ditawarkan oleh parpol. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka juga lebih sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk (Mahmud MD,2009;108). Hal-hal mengenai susunan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya diserahkan pengaturannya lebih lanjut kepada undang-undang oleh UUD 1945 (Pasal 19 ayat (2)). Lebih lanjut berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang sedikitnya sekali dalam setahun. Artinya selama setahun Dewan Perwakilan Rakyat, jika karena kebutuhan yang memang diperlukan, maka dapatlah kemudian mengadakan sidang lebih dari sekali, hal mana sangat tergantung daripada intensitas kebutuhan untuk mengadakan sidang-sidang, dengan tujuan memperlancar daripada tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Karena sidang DPR dipersyaratkan hanya paling sedikit sekali dalam setahun, sedangkan dalam ketentuan tersebut ternyata tidak ditegaskan dimana tempat Dewan Perwakilan Rakyat bersidang. Hal mana tentunya akan berbeda dengan ketentuan yang mengatur tempat Majelis Permusywaratan Rakyat untuk bersidang, yaitu di ibu kota negara (Jakarta). Mungkin saja nantinya Dewan Perwakilan Rakyat akan mengadakan sidang tidak hanya di Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara, namun bisa saja dilakukan di daerah lainnya di Indonesia, oleh dikarenakan dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum serta adanya kebutuhan mendesak untuk itu, yang tentunya semua itu mendapatkan kesepakatan bersama. Selanjutnya akan dikutipkan dalam kententuan UU No. 27 Tahun 2009, yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPR dan selanjutnya akan dibahas seperlunya, dengan tujuan hanya untuk membandingkan antara ketentuan yang ada dalam UUD 1945 dengan ketentuan UU tersebut. Berkaitan dengan tugas dan wewenang DPR, dalam ketentuan Pasal 71 UU No. 27 Tahun 2009, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang DPR adalah. a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
I Gusti Ngurah Santika, SPd
294
c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; d. membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; e. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; f. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; g. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden; h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN; i. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; j. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang; k. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi; l. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain; m. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
I Gusti Ngurah Santika, SPd
295
n. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; o. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial; p. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; q. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden; r. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; s. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang. Pada saat berlangsungnya amandemen pertama terhadap UUD 1945, yang bertujuan untuk mengurangi kekuasaan eksekutif, serta mengembalikan fungsi-fungsi kelembagaan negara, agar sesuai dengan hakekat dari fungsi yang seharusnya melekat dan dijalankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Bentuk pengurangan kekuasaan sebagaimana kemudian dilakukan oleh MPR, yang salah satunya adalah dengan cara mengembalikan kekuasaan membentuk undang-undang, dimana sebelumnya ada pada Presiden kemudian dialihkan kepada DPR, kemudian untuk selanjutnya Presiden hanyalah memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu dapatlah dilihat kemudian dalam ketentuan Pasal 20 UUD 1945, yang di dalamnya terdiri dari 5 ayat, bunyinya yaitu. 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan masa itu. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
296
undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (kursif penulis). Pasca-amandemen UUD 1945, telah terjadi pergeseran posisi dan kewenangan kelembagaan negara, terutama berkaitan dengan kewenangan kelembagaan negara dalam bidang pembentukan undang-undang, yaitu antara legislatif dan eksekutif. Pada mulanya kekuasaan daripada eksekutif, baik secara normatif maupun dalam tataran praktis, kedudukannya jauh lebih dominan dibandingkan legislatif, kemudian setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, khususnya terhadap pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka kekuasaan eksekutif bergeser ke arah sebaliknya, dimana legislatif memiliki kedudukan yang cukup untuk berhadapan secara langsung dengan lembaga eksekutif, dalam membentuk undang-undang meskipun dengan bentuk persetujuan bersama. Bahkan, DPR sebagai lembaga legislatif kemudian lebih punya dasar kewenangan yang jelas dan konstitusional, khususnya kewenangan dalam bidang pembentukan undangundang. Kewenangan di wilayah legislasi tersebut, dapatlah kemudian ditemukan pada amandemen pertama terhadap UUD 1945, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 oleh MPR. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, menegaskan poin yang sifatnya mendasar dalam kewenangan pembentukan undang-undang. Sehingga mulai tanggal 19 Oktober 1999, terkait dengan kekuasaan dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi) terletak di tangan DPR, bukan pada Presiden seperti sebelumnya. Tentunya MPR dengan sadar telah berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi DPR pada posisi yang sebenarnya. Karena DPR sebagai lembaga negara yang pada dasarnya merupakan perwakilan rakyat yang berdaulat, sudah seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk membentuk undangundang, sehingga nantinya undang-undang akan benar-benar merupakan produk dari rakyat. Dengan demikian, rakyat sendirilah yang kemudian memberikan persetujuan terhadap peraturan tersebut, terutama untuk mengikatkan dirinya pada undang-undang yang dibentuk oleh DPR sebagai wakilnya. Menurut Mahmud MD (2010;271) bahwa lembaga legislatif adalah parlemen yang merupakan pembuat UU sesuai dengan kehendak rakyat. Di dalam negara demokrasi, rakyatlah yang menentukan hukum melalui wakil-wakilnya diparlemen yang dipilih langsung oleh rakyat sendiri. Namun, sistem pemerintahan yang digunakan di sini bukanlah badan legislatif, yang tunduk kepada kontrol rakyat secara langsung dengan hak suaranya. Biasa kontrol langsung sebagaimana dimaksudkan penulis di atas adalah berkaitan dengan undang-undang yang oleh rakyat dapat dilberlakukan dengan berbagai bentuk/cara. Misalnya dengan referendum obligator atau dengan referendum fakultatif. Pada referendum obligator berlakunya undang-undang tergantung atas izin rakyat sendiri, yang diberikan secara suara terbanyak. Referendum fakultatif
I Gusti Ngurah Santika, SPd
297
terdapat, apabila aturan yang telah ditetapkan oleh alat legislatif hanya tunduk kepada suara rakyat, apabila dalam waktu yang tertentu sesudah undang-undang itu diumumkan sejumlah tertentu orang-orang yang berhak bersuara menghendaki hal ini (Kranenburg,1983;103). Demokrasi dengan sistem pengawasan oleh rakyat dengan referendum ini, terdapat dalam negara Swiss. Dimana dalam hal semua kekuasaan yang menentukan ada di tangan rakyat. Pembuatan undang-undang/peraturan/keputusan menjadi lebih lambat dan ruwet. rakyat dengan hak referendumnya dapat menilai dan menentukan apakah suatu undang-undang dasar ataupun undang-undang biasa dapat diperlakukan atau tidak. Pada umumnya rakyat biasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai/menguji apakah suatu peraturan/undang-undang itu baik atau tidak, memenuhi hasrat kesadaran hukum rakyat dan syarat-syarat lainnya (Azhary,1986;66-67). Dilain pihak, kenyataannya dalam memberikan penilaian terhadap suatu undang-undang, berkaitan dengan syarat-syarat apakah undang-undang itu adalah baik atau tidak, tentunya memerlukan suatu keahlian yang sangat khusus, agar dapatlah memberikan suatu penilaian yang sifatnya objektif serta sesuai dengan tujuan dari lahirnya peraturan tersebut. Lebih lanjut mengenai pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang, yang tentunya akan berbeda secara signifikan, dengan format kekuasaan kelembagaan negara yang diatur pada dokumen awal UUD 1945, yaitu pada saat UUD 1945 belum diamandemen. Ketentuan tersebut telah mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 pra-amandemen, yang menyatakan pada dasarnya bahwa Presiden memegang kekuasaan pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR. Hal mana tentunya akan berbeda dengan sesudah perubahan terhadap UUD 1945 tepatnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Kemudian terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, menurut Soeprapto (2007;118) bahwa Hamid S. Attamimi berpandangan, makna Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) pada dasarnya menegaskan posisi Presiden sebagai pemegang legislative power (dalam pembentukan undang-undang), sedangkan DPR melaksanakan (memberikan) persetujuan secara bersama-sama. Dengan demikian kewenangan pembentukan undang-undang ada di tangan Presiden. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan sebenarnya memiliki makna yang sangat penting bila hal tersebut dipandang dari sudut negara demokrasi, dimana kekuasaan pembentukan undang-undang berada di tangan lembaga legislatif, sebagai simbol daripada kedaulatan rakyat. Ternyata oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen, telah meletakan kekuasaan pembentukan undang-undang berada pada tangan eksekutif. Namun, kemudian jika disimak kembali dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, walaupun dinyatakan bahwa Presiden
I Gusti Ngurah Santika, SPd
298
berkedudukan sebagai pemegang kekuasan untuk membentuk undang-undang, namun perlulah diketahui bahwa tanpa adanya kehendak daripada DPR, berupa persetujuan dalam bidang pembentukan undang-undang, maka tentunya kekuasaan Presiden dalam bidang pembentukan undang-undang, tidak akan dapat dilaksanakan kemudian (lihat ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebelum perubahan). Hanya saja seolah-olah pada saat Orde Baru berkuasa, dengan rekayasa yang dibuatnya, terutama dalam pengisian keanggotaan dalam lembaga legislatif, disertai pula dengan dukungan kekuatan dari ABRI, Golkar dan Birokrasi, telah menafsirkan secara sepihak terhadap ketentuan konstitusional tersebut. Tentunya hal tersebut cenderung semakin melemahkan dan menyudutkan DPR di mata Presiden pada waktu itu. Sehingga ketentuan tersebut, hal mana sebenarnya diperlukan persetujuan dari DPR, terutama kewenangan Presiden dalam memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, tidak berjalan dengan baik. Dimana seolaholah, setiap Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, maka DPR harus menyetujuinya. Karena memang ketika itu terlihat seperti tidak adanya pilihan lain, selain hanya dengan menyetujui semua rancangan undang-undang yang kemudian diajukan oleh Presiden. Setidaknya, dengan pengalaman pahit di masa lalu tersebutlah, tentunya telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, maka untuk itu kita perlu membenahi kembali struktur ketatanegaraan, khususnya berkaitan dengan pembagian kekuasaan (distribution of power), agar nantinya betul-betul sesuai dengan ketentuan negara yang pada dasarnya menganut asas-asas demokrasi, seperti adanya mekanisme checks and balaces antar lembaga-lembaga negara. Semua keinginan tersebut tentunya hanya bisa tercapai, yaitu dengan cara mengembalikan kedaulatan rakyat untuk membentuk undang-undang, khususnya dengan merubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, yang berarti meletakan kekuasaan untuk pembentukan undang-undang berada di tangan DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Oleh karenanya, DPR sebagai lembaga legislatif dengan tegas telah digariskan oleh UUD 1945, merupakan pemegang kekuasaan dalam bidang pembentukan undangundang. Sedangkan untuk pemerintahan hanya bertugas untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk dibahas bersama sampai mendapatkan persetujuan bersama. Dalam pembentukan undang-undang itu, DPR lah yang disebut legislator, sedangkan pemerintah merupakan co-legislator, karena setiap rancangan undang-undang untuk ditetapkan menjadi undang-undang memerlukan pembahasan dan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden (Asshiddiqie,2006;31). Dengan demikian, jika kita simak secara sepintas, memanglah terlihat seolah-olah bahwa DPR lah yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 itulah, yang kemudian diubah menjadi,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
299
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (kursif penulis). Dan, rancangan undang-undang tersebutlah untuk kemudian dibahas kembali untuk mendapatkan persetujuan bersama, oleh DPR dengan Presiden (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945). Pergeseran kekuasaan eksekutif dari pemegang kekuasaan menjadi sekedar hak mengajukan rancangan idealnya dapat dipandang sebagai salah satu berkah daripada reformasi, yang telah mengantarkan, bahkan berhasil mentransformasikan sistem ketatanegaraan Indonesia pada arah yang lebih baik. Keseimbangan kekuasaan, baik antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun institusi kenegaraannya lainnya akhirnya lebih mengarah pada hubungan interelasi yang berada pada posisi seimbang dalam kerangka checks and balances system. Sehingga, patut dikatakan kemudian bahwa amandemen konstitusi tersebut akan berimplikasi besar terhadap perubahan sistem hukum dan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan masalah ketatanegaraan, terutama dalam pembentukan undang-undang. Dalam ketentuan ayat (2) dari Pasal 20 UUD 1945, telah mengatur kerjasama antara DPR dengan Presiden untuk membentuk undang-undang, terlihat bahwa UUD 1945 dalam kenyataannya memberikan kesempatan pula, kepada eksekutif untuk ikut terlibat secara langsung dalam pembentukan undang-undang. Dengan adanya ketentuan demikian, maka eksekutif dapat ikut berpartisipasi untuk membentuk undang-undang, yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya di lapangan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pihak eksekutif dalam kenyataannya selalu lebih tahu tentang kebutuhan rakyat, serta dapat bertindak cepat untuk menanggapi suatu perubahan yang terjadi secara cepat, hal mana tentunya sangat berbeda dengan legislatif, dikarenakan oleh terlalu besarnya jumlah anggota dalam badan ini, menyebabkan dalam pengambilan keputusan menjadi berlarut-larut. Terkait dengan pembentukan undang-undang yang melibatkan Presiden dalam pembahasannya, di samping adanya DPR yang merupakan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Maka dari hal tersebut, kemudian Kelsen (2011;383) berpendapat bahwa suatu organ adalah organ legislatif, sepanjang organ ini diberi wewenang untuk membuat norma hukum yang umum. Tidak pernah terjadi dalam realita politik, bahwa semua norma umum dari suatu tatanan hukum nasional, harus dibuat secara eksklusif oleh satu organ yang disebut lembaga legislatif. Pernyataan Kelsen tersebut menggambarkan, bahwa dalam pembentukan norma umum, khususnya undang-undang (norma umum), tidak hanya dapat diberikan kepada satu lembaga negara saja, seperti hanya pada lembaga legislatif (DPR), namun juga dipandang perlu, untuk memberikan kepada Presiden berupa suatu kewenangan untuk secara langsung terlibat dalam membentuk undang-undang, bahkan selanjutnya ditugaskan untuk membentuk peraturan yang berfungsi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
300
untuk menjalankan undang-undang tersebut. Bentuk keterlibatan Presiden untuk dapat membentuk undang-undang, dikarenakan dalam pengambilan keputusan lembaga legislatif seringkali lamban, sedangkan dipihak lain kebutuhan akan undang-undang bagi rakyat, untuk mengatur kehidupan sudah benar-benar diperlukan, bahkan undang-undang yang dimaksud, juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyejahterakan rakyat. Sehingga, kebutuhan daripada pemerintah yang sifatnya mendesak terutama untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, tentunya memerlukan landasan hukum yang jelas. Karena dalam melakukan berbagai tindakan pemerintah haruslah selalu berdasar pada hukum, yang telah ada terlebih dahulu, adanya ketentuan tersebut merupakan ciri daripada suatu negara yang meletakan hukum pada posisi tertinggi. Indonesia adalah negara hukum, maka tentunya berkaitan dengan segala aspek kehidupan, baik menyangkut dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, tentunya termasuk pula dalam bidang menyelenggarakan pemerintahan, haruslah berdasarkan atas hukum, hal mana hukum tersebut pun, harus sesuai pula dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Sistem hukum nasional merupakan hukum, yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang tentunya saling menunjang, satu dengan yang lain, dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi segala permasalahan, yang timbul kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentunya untuk sekarang ini, berkaitan dengan permasalahan yang mungkin timbul dalam negara modern adalah bersifat sangat kompleks. Mungkin saja tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan memberikan kewenangan, untuk membentuk undang-undang yang nantinya akan menyelesaikan permasalahan tersebut, hanya kepada satu lembaga negara, yakni DPR. Karena belum tentu apa yang kemudian dikehendaki oleh rakyat untuk diselesaikan, ternyata tidaklah dapat dirumuskan secara sempurna oleh lembaga legislatif, yang notabene telah ditentukan untuk berada di pusat negara, sedangkan rakyat sendiri sebenarnya merupakan orang yang diwakilinya, ternyata berada jauh di daerah-daerah. Bahkan, banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang terpilih menjadi anggota legislatif tersebut, bukanlah orang-orang yang pada dasarnya ahli, dikarenakan mereka adalah orang-orang dipilih secara politik. Hal mana akan berbeda dengan eksekutif, yang tersebar ke seluruh penjuru negara, serta memiliki perlengkapan dan tenaga ahli yang cukup, untuk membentuk suatu peraturan guna menyesuaikan dengan kebutuhannya, dalam menyelenggarakan tugas-tugas negara terutama untuk menyejahteraan rakyat. Untuk itu, dapat kemudian dikatakan bahwa undang-undang memiliki kedudukan dan peranan yang penting, dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Walaupun pada saat yang sama ada
I Gusti Ngurah Santika, SPd
301
konstitusi, namun tidaklah mungkin dapat dijalankan secara langsung sepenuhnya sesuai dengan apa yang kemudian tercantum di dalamnya. Bahkan, seringkali konstitusi sendiri memberikan kesempatan, kepada peraturan yang ada di bawahnya, untuk mengatur selanjutnya berkaitan dengan masalah apa saja yang memang belum dapat diatur di dalam konstitusi tersebut. Dengan demikian, undang-undang bisa dikatakan memiliki fungsi dan peranan yang besar dalam menjalankan amanat dari konstitusi. Tentunya sebagai sebuah atribusi dari konstitusi, maka undang-undang akan memiliki karakteristik, yang tentunya berbeda dengan produk hukum lainnya, karena lembaga yang membentuknya tidak diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan di dalam konstitusi. Agar tidak keliru, maka terkait dengan undang-undang, Hardjasoemantri (1986;75) berpendapat bahwa undang-undang memiliki karakteristik yaitu (1) sederhana, tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat; (2) mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar untuk peraturan pelaksanaannya lebih lanjut; (3) mencakup semua segi agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan masing-masing segi lebih lanjut. Dengan demikian, jelaslah bahwa kewenangan apa yang kemudian telah digariskan oleh UUD 1945, kepada DPR dan Presiden sebagai dua lembaga negara yang berkompetensi untuk membuat undang-undang, berdasarkan kewenangan selanjutnya, seperti apa yang telah diatribusikan oleh UUD 1945, dalam bentuk peraturan yang posisinya tepat berada di bawahnya. Tugas yang dijalankan oleh DPR dan Presiden merupakan tugas konstitusional, hal mana dikarenakan untuk dapat menjalankan sebuah garis hukum dalam suatu pasal UUD, maka pihak yang berkuasa dalam negara memerlukan ketetapan-ketetapan undang-undang yang didasarkan atas pasal UUD (Hazairin,1981;38). Dengan kata lain, bahwa sebagai hukum dasar yang tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 tersebut hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis besarnya saja (Marbun,2003;14). Pendapat-pendapat tersebut di atas adalah sesuai dengan bunyi dari Penjelasan UUD 1945 sebelum di hapus, yang menyatakan bahwa UUD 1945 adalah singkat dan supel, artinya hanya memuat garis besarnya saja. Bunyi selengkapnya. Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina. Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lainlain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum
I Gusti Ngurah Santika, SPd
302
dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut. Demikianlah sistem Undang-Undang Dasar. Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin supel (elastic) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang (verouderd). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang (kursif penulis). Dengan demikian, pengaturan dinamika ketatanegaraan selanjutnya, utamanya berkaitan dengan kebutuhan rakyat, telah diserahkan pengaturannya lebih lanjut kepada undang-undang, yang kemudian dibentuk bersama oleh DPR dan Presiden. Oleh karena itu, undang-undang merupakan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang berada di dalam UUD 1945, pada dasarnya merupakan buah hasil dari kerjasama antara DPR dan pemerintah, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama di antara kedua lembaga negara tersebut. Bahkan menurut Soepomo (1954;107) bahwa undang-undang adalah selalu hasil perbuatan bersama antara Pemerintah dan DPR. Dengan demikian,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
303
hanya DPR dan Presiden saja yang memiliki kewenangan untuk membentuk undangundang sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut adalah sesuai dengan asas kelembagaan yang kemudian dimaksud dalam ketentuan dari Pasal 5 huruf b UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundangundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang (kursif penulis). Kewenangan DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang, merupakan bentuk formal daripada undangundang, jika hal tersebut dilihat dari sudut pandang siapa yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, tanpa adanya kerjasama dari kedua lembaga negara tersebut dalam membentuk undang-undang, maka tidak mungkin ada suatu rancangan undang-undang, yang kemudian dapat menjadi undangundang. Dengan demikian, intinya secara konstitusional kedudukan antara DPR RI dan Pemerintah telah mencerminkan keseimbangan/kesetaraan (Sekjen DPR RI,2010;32). Oleh karena itu, DPR dalam pembentukan undang-undang, kedudukannya adalah sejajar dengan Presiden. Tentunya, selain adanya keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang, nantinya juga keseimbangan tersebut tercermin pula dalam tugas-tugas lainnya, baik yang telah ditentukan oleh UUD 1945 maupun dalam undangundang yang akan dibentuk berdasarkan UUD 1945. Terdapatnya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), di antara kedua lembaga negara tersebut, merupakan salah satu tujuan diamandemennya UUD 1945. Dengan demikian, sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kedudukan sederajat dengan Presiden (Soemantri,1993;126). Setidaknya penulis berpendapat, bahwa dengan adanya ketentuan dari Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, ternyata terlihat ketentuan tersebut telah memberikan suatu keseimbangan antara Presiden dan DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, tidak akan ada sebuah undang-undang yang lahir kemudian, tanpa mendapatkan persetujuan bersama, antara DPR dan Presiden, sehingga kedua lembaga negara tersebut harus bekerjasama untuk mencapai persetujuan bersama sampai akhirnya terbentuk sebuah undang-undang. Oleh karena itu, tanggungjawab dalam membentuk undang-undang tidaklah sepenuhnya berada pada pundak DPR, dikarenakan Presiden menurut UUD 1945, ternyata ikut pula secara langsung memikul tanggungjawab dalam membentuk undang-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
304
undang. Sangat penting untuk dikemukakan bahwa berdasarkan konstitusi maupun politik riil, lembaga legislatif bukan hanya DPR. Sebab menurut UUD 1945, DPR hanya setengah dari seluruh lembaga legislatif, sedangkan yang separuhnya lagi adalah Presiden. Jadi, Presiden sebenarnya memiliki kekuatan legislasi yang sama dengan seluruh anggota DPR yang berjumlah 550 orang (Mahmud MD,2010;289). Kendati di sisi lain ternyata sebagian kalangan berpendapat, Presiden masih punya posisi yang cukup dominan, terlihat dengan tersiratnya kewenangan veto. Namun, setidaknya penegasan daripada ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa legislative power saat ini ada di tangan legislatif, akan semakin memperkuat posisi DPR. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, misalnya jika ditinjau dari tafsir gramatikal atas pasal tersebut, seolah-olah telah memberikan kepada Presiden berupa kewenangan yang bersifat penuh, untuk menolak atau menyetujui pada saat rancangan undang-undang dibahas bersama DPR. Dalam bahasa berbeda, hak ini tentunya mirip dengan konsep veto, yang diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Amerika Serikat. Selanjutnya ditegaskan kembali terkait upaya mekanisme yang berbentuk saling mengimbangi antara DPR dan Presiden, dalam bidang pembentukan undang-undang. Hal tersebut tercantum sangat jelas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945, ketentuan tersebut merupakan suatu kelanjutan daripada proses untuk mencapai persetujuan bersama sebagaimana dimaksudkan sebelumnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Seandainya nanti jika ternyata ada suatu rancangan undang-undang, baik yang diajukan oleh Presiden, kemudian dalam kenyataannya tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maupun sebaliknya, maka rancangan undang-undang yang sebelumnya diajukan oleh DPR maupun Presiden, yang tidak mendapatkan persetujuan bersama tersebut, tentunya kemudian terkait dengan rancangan undang-undang tersebut, tidaklah dapat lagi untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada periode itu. Jika kita lihat kembali, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, maka tidak tampaklah bahwa hanya DPR saja yang sebenarnya memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Terlihat, DPR dan Presiden sama-sama punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang, lewat persetujuan bersama sebagai mana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Yang ternyata, jika tidak tercapai persetujuan bersama tentang rancangan undang-undang dari DPR maupun Presiden tersebut, tentunya rancangan undang-undang baik yang berasal dari DPR maupun dari Presiden tersebut, tidak akan dapat diajukan lagi untuk dibahas dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Jadi, tegasnya bahwa terkait dengan rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan bersama tersebut, tidak dapat lagi diajukan untuk dibahas kembali pada periode keanggotaan DPR tersebut. Dengan kata
I Gusti Ngurah Santika, SPd
305
lain, setelah masa keanggotaan DPR tersebut, tentunya rancangan undang-undang itu dapat diajukan kembali untuk dibahas sampai akhirnya mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Ketentuan ini dapat kita lihat kembali dalam UU No. 12 Tahun 2011, tepatnya dalam ketentuan Pasal 69 ayat (3), yang menyatakan bahwa : Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu (kursif penulis). Mekanisme yang sebenarnya dianut UUD 1945 adalah dalam kerangka checks and balances, penafsiran tersebut berasal dari ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa jika dalam kenyataannya suatu rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak dapat diajukan pada periode keanggotaan DPR tersebut. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tanpa ada persetujuan bersama, tidak akan ada rancangan undang-undang yang kemudian dapat diselesaikan menjadi undangundang. Untuk itu, diperlukan suatu kerjasama yang apik antara Presiden dan DPR, untuk membentuk undang-undang. Kerjasama dimaksudkan di sini, tentunya merupakan kerjasama yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi rakyat, bukannya kerjasama dalam rangka membentuk undang-undang, yang isinya hanya untuk memenuhi kepentingan daripada elit-elit penguasa, hal mana berpotensi merugikan kepentingan rakyat banyak. Selanjutnya, dalam ketentuan ayat (4) dari Pasal 20 UUD 1945, menentukan dengan tegas bahwa jika suatu rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, untuk menjadi undang-undang harus disahkan kembali oleh Presiden. Pengertian yang dapat penulis tangkap dalam hal ini, pertama, bahwa adanya ketentuan bagi Presiden untuk kemudian mengesahkan rancangan undang-undang, merupakan suatu yang bersifat keharusan bagi Presiden, dengan kata lain, bahwa ketentuan tersebut sifatnya imperative (memaksa), kedua, bahwa tanpa disahkan oleh Presiden, suatu rancangan undang-undang yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tidak akan pernah menjadi undang-undang. Sehingga, dengan dasar pemikiran tersebut maka untuk berlakunya suatu rancangan undang-undang, dipandang perlu untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden dalam bentuk tanda tangan, yang selanjutnya memerintahkan pengundangannya dalam lembaran negara. Terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang, Simanjuntak (1981;23) menyatakan bahwa rancangan undang-undang selalu memerlukan pengesahan Presiden bila menjadi undang-undang. Dengan kata lain, suatu rancangan undang-undang hanya dapat mengikat umum jika rancangan undang-undang telah mendapatkan suatu pengesahan dari Presiden, dengan adanya pengesahan dari Presiden tersebut maka berlakulah asas bahwa
I Gusti Ngurah Santika, SPd
306
ketidaktahuan akan undang-undang tidak memaafkan seseorang dari kesalahannya. Namun, terlihat kemudian dalam ketentuan ayat (5) dari Pasal 20 UUD 1945, telah memberikan pilihan yang boleh dikatakan tegas, dengan tidak memberikan kesempatan kepada Presiden, untuk bertindak lain daripada ketentuan ayat (4) dari Pasal 20 UUD 1945, yaitu menandatangani rancangan undang-undang yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama. Dengan adanya ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 tersebut, sebenarnya Presiden memiliki hak untuk tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Namun, dilain pihak telah menegaskan tentang komitmen yang dibuat antara DPR dan Presiden sebelumnya dalam bentuk persetujuan bersama akan mengikat kedua belah pihak, sehingga mau tidak mau rancangan undang-undang, yang telah mendapat persetujuan bersama sebelumnya, akan menjadi undang-undang, terlepas dari ditandatangani atau tidaknya rancangan undang-undang tersebut oleh Presiden. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis berpendapat dengan adanya ketentuan ayat (5) dari Pasal 20 UUD 1945, telah memberikan jalan bagi rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah mendapat persetujuan bersama, menurut ketentuan ayat (2) dari Pasal 20 UUD 1945, untuk menjadi undang-undang, walaupun tanpa mendapat suatu pengesahan dari Presiden. Dengan kata lain, jika suatu rancangan undang-undang telah mendapat persetujuan bersama, maka setelah itu, hanya tinggal menunggu waktu pemberlakuannya saja, yang mana hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945, dengan menentukan dua jalan bagi pemberlakuan sebuah rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Pertama, Presiden menurut ketentuan ayat (4) dari Pasal 20 UUD 1945, akan memberlakukan rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadi undang-undang, dengan membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan Presiden dalam pemberlakuan rancangan undang-undang tersebut dan kemudian memerintahkan untuk diundangkan dalam negara. Kedua, adanya ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang memberikan batas waktu kepada suatu rancangan undang-undang, yang telah mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadi undang-undang, yang dalam konstitusi telah ditentukan yaitu selama 30 hari setelah mendapatkan persetujuan bersama untuk diundangkan dalam lembaran negara. Dengan begitu, baik ditanda tangani atau tidak oleh Presiden terhadap rancangan undangundang yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden tersebut, akan tetap menjadi undang-undang dengan sendirinya. Dengan demikian, adanya pengaturan berupa ketentuan ayat (5) dari Pasal 20 UUD, sebenarnya telah menegaskan kembali kekuatan daripada ketentuan ayat (2) dari Pasal 20 UUD 1945, dimana jika suatu rancangan undang-undang sudah mendapatkan persetujuan bersama
I Gusti Ngurah Santika, SPd
307
antara DPR dan Presiden, maka dalam kenyataannya jika ketentuan ayat (4) dari Pasal 20 UUD 1945 tidak dilaksanakan oleh Presiden, maka ketentuan dari Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 tidak memberikan toleransi kepada Presiden, untuk tidak mengundangkan rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama. Karena ketentuan ayat (5) dari Pasal 20 UUD 1945 telah memerintahkan dalam waktu tiga puluh hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, agar selanjutnya rancangan undang-undang tersebut diundangkan sebagaimana mestinya dalam lembaran negara, sehingga tentunya akan mengikat seluruh komponen negara, untuk melaksanakannya secara konsekuen, tanpa alasan untuk setuju atau tidak setuju dengan undang-undang yang lahir tersebut. Karena undang-undang tersebut sudah ditempatkan dalam lembaran negara, sehingga tentunya akan mengikat siapa saja yang berada di wilayah tempat peraturan tersebut berlaku. Ketentuan yang mengatur mengenai pengesahan suatu rancangan undangundang untuk kemudian menjadi undang-undang, diatur pula dalam UU No. 12 Tahun 2011, tepatnya dapatlah diketahui kemudian pengaturannya dalam ketentuan Pasal 72 dan 73 dari UU No. 12 Tahun 2011, bunyi pasal sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Pasal 72 1. Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 2. Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (kursif penulis) Pasal 73 1. Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. 2. Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. 3. Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
308
berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (kursif penulis). Selanjutnya berkenaan dengan fungsi DPR di dalam UUD 1945, setidaknya ditentukan dengan jelas bahwa terdapat tiga fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga fungsi tersebut meliputi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan (control), dan fungsi penganggaran (budgeting) (Pasal 20A ayat (1) UUD 1945). Ketiga fungsi tersebut dimandatkan kepada DPR oleh UUD 1945, dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan yang menjalankan fungsi perwakilan (representation). Artinya, representasi haruslah selalu menjadi pilar utama, dalam setiap pelaksanaan fungsi DPR. Sehingga, dalam menjalankan segala tindakannya, DPR haruslah terlebih dahulu melihat rakyat sebagai konstituennya, yang sebelumnya telah memberikan legitimasi kepadanya, dalam bentuk dukungan suara pada saat diselenggarakannya pemilu legislatif, semua itu merupakan bentuk daripada pertanggungjawaban DPR baik dilihat secara politis dan moral. Dalam Penjelasan Pasal 79 huruf k, UU No. 27 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya (kursif penulis). Semua pengaturan tersebut juga terdapat dalam ketentuan Pasal 69 UU No. 27 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa. 1. DPR mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan. 2. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat (kursif penulis) Setidaknya rakyat telah mempercayakan kepada DPR, untuk melakukan fungsifungsinya sesuai dengan UUD 1945, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak rakyat, dalam berhadapan dengan pemerintah. Misalnya saja dapat dilakukan dengan cara menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Pasal 71 huruf s, UU No.27 Tahun 2009). Selanjutnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20A ayat, (2), dan (3) UUD 1945, yang merupakan kewenangan DPR untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban konstitusionalnya agar sistem demokrasi tidak keluar dari jalurnya.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
309
Menurut Asshiddiqie (2006;31-32) ada tiga hal penting yang musti diatur oleh lembaga lembaga perwakilan rakyat, yaitu; (i) Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan (iii) Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR selanjutnya diwujudkan dalam empat kegiatan berikut: 1. Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation); 2. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process); 3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval); 4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents) (Asshiddiqie,2006;32). Berkaitan dengan fungsi penganggaran pada dasarnya dapatlah dikatakan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri. Meskipun rancangan APBN selalu datang dari pihak eksekutif (presiden), pada akhirnya setiap pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, akan selalu dituangkan ke dalam sebuah undang-undang tentang APBN. Artinya, hal ini sebenarnya identik dengan pelaksanaan kewenangan fungsi legislasi daripada DPR. Fungsi penganggaran bersinggungan pula dengan fungsi pengawasan, sebab DPR memiliki kewenangan, untuk mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, ketika sudah ditetapkan tentunya. Sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditemui kembali dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan (3) UU No. 27 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa. 2. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. 3. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN (kursif penulis). Agar kekuasaan eksekutif tidak dalankan secara despotis atau sewenang-wenang, maka diperlukanlah kemudian berupa mekanisme kontrol dari lembaga perwakilan (DPR). Secara teoritik kewenangan mengawasi yang dimiliki oleh DPR dapat dirinci sebagai berikut: 1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making);
I Gusti Ngurah Santika, SPd
310
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing); 3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of budgeting); 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control of budget implementation); 5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government performances); 6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public officials), dalam bentuk persetujuan atau penolakan, atau pun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR. (Saptaningrum, 2011;34). Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, Mahendra (1996;59) kemudian berpendapat bahwa kedudukan DPR yang kuat secara konstitusional memberikan jaminan bagi pelaksanaan fungsi DPR yang mencakup fungsi pembuatan undang-undang, penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara dan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Tidak lain dikarenakan kedua lembaga tersebut merupakan dua organ yang memang kedudukannya sejajar, bahkan terpisah satu sama lainnya. Menurut Ranadireksa (2009;133) bahwa sisi positif dari kedudukan legislatif yang terpisah dengan eksekutif adalah bahwa legislatif dapat melakukan fungsi kontrolnya secara lebih obyektif (dalam sistem parlementer sebagai (besar) legislatif memiliki kepentingan yang sama dengan eksekutif. Lebih lanjut kemudian mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, dapat kemudian dilakukan dalam bentuk: pertanyaan parlementer (hak mengajukan pertanyaan), interpelasi, angket (enquete), dan mosi (impeachment/pemakzulan). Ketentuan Pasal 20A UUD 1945 sebagaimana dimaksudkan di atas, merupakan fungsi daripada DPR, seperti apa yang kemudian diamanatkan oleh UUD 1945. Selain ketentuan tersebut, dalam kenyataannya terdapat 3 ayat lagi yang berkenaan dengan hakhak DPR untuk menunjang tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud di atas. Berikut ini merupakan hak-hak konstitusional DPR lainnya yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (2), (3), (4) UUD 1945, yaitu. 2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. 4. ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
311
Dalam hal ini perlulah dibedakan antara hak Dewan Perwakilan Rakyat dengan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat di dalam ketentuan Pasal 20A UUD 1945, menurut pengertian pertama merupakan hak secara kelembagaan, sedangkan untuk pengertian kedua merupakan hak perseorangan yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis,dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: 1. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; 2. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket 3. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atauWakil Presiden. Hak mengajukan pertanyaan menurut Penjelasan UU No. 27 Tahun 2009, adalah Hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR. Hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapa pun didalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat. Hak imunitas merupakan hak anggota DPR untuk tidak dapat dituntut secara hukum atas pendapat yang dinyatakan dalam sidang. Selain itu, dalam undangundang juga ditentukan tentang hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seperti hak protokoler, yang dimaksud dengan hak protokoler adalah hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya, baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Lebih rinci terkait dengan hak anggota DPR terdapat dalam ketentuan Pasal 78 UU No. 27 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa anggota DPR mempunyai hak:
I Gusti Ngurah Santika, SPd
312
a. Mengajukan usul rancangan undang-undang; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan pendapat; d. Memilih dan dipilih; e. Membela diri; f. Imunitas; g. Protokoler; dan h. Keuangan dan administratif. Selain yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 20A UUD 1945, ternyata DPR juga memiliki beberapa kewenangan lainnya, terkait dengan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Kewenangan ini kemudian diatur secara tersebar pada beberapa pasal dalam UUD 1945 dan juga dalam undang-undang yang mengatur tentang DPR seperti apa yang dinyatakan di atas. Misalnya, kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan kepada Presiden dalam menyatakan perang (Pasal 11 ayat (1) UUD 1945), membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar terkait dengan beban keuangan negara, ataupun yang berkaitan dengan undang-undang baik berupa perubahan maupun pembentukannya (Pasal 11 ayat (2) UUD 1945), memberikan pertimbangan kepada Presiden baik dalam mengangkat duta maupun menerima penempatan duta negara lain (Pasal 13 ayat (1), dan (2) UUD 1945), memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberi amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Tugas ini juga merupakan salah satu fungsi DPR sebagai lembaga legislatif yang bertugas dalam bidang pengawasan terhadap tindakan Presiden. Oleh karena itu, Latupapua (2008;16) kemudian berpendapat bahwa fungsi parlemen sebagai penyeimbang kedaulatan rakyat atas supremasi lembaga kepresidenan. Selain itu, DPR mempunyai fungsi yang penting dan strategis, seperti memberikan persetujuan atas rancangan APBN yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden setelah memperhatikan petimbangan dari DPD (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945), sebenarnya tugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menurut Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus disebut sebagai hak begrooting, adalah juga merupakan tugas daripada DPR dalam bidang perundang-undangan. Bedanya terletak pada inisiatif pembuatan rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus berasal dari pemerintah. Karena pemerintah dengan segala aparat dan perlengkapannya lebih mengetahui apa yang harus dilakukan dalam usahanya melaksanakan program kerjanya (Busro dan Busroh,1985;112). Bahkan, jika kita lihat pengaturan dalam ketentuan Pasal 23 Bab VII tentang Hal Keuangan, khususnya pada ketentuan ayat (3) menyatakan Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
I Gusti Ngurah Santika, SPd
313
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun yang lalu(kursif penulis). Dengan demikian, UUD 1945 telah meletakan kekuasaan yang begitu besar pada DPR dalam hal bidang penetapan APBN, dikarenakan APBN sendiri memang menyangkut uang rakyat, yang perlu kemudian diawasi penggunaannya. Sebelum UUD 1945 diamandemen dalam Penjelasan UUD 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara menyatakan Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lainlainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (kursif penulis). Selain tugas tersebut di atas, DPR memilih untuk mengisi keanggotaan BPK setelah memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat (1) UUD 1945), tentunya dalam hal pertimbangan yang diberikan oleh DPD kepada DPR terkait dengan pengangkatan anggota BPK tidak mengikat DPR dalam mengambil keputusan. Sehingga untuk itu, DPR tidaklah harus mengikuti pertimbangan DPD dalam hal pengangkatan anggota BPK, karena hanya merupakan suatu pertimbangan, yang tentunya tidak mengikat secara hukum. Selain itu, DPR juga memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang sebelumnya diusulkan oleh KY (Pasal 24A ayat (3) UUD 1945), dalam hal ini tentunya akan memiliki makna yang berbeda, apabila kata persetujuan tidak diberikan oleh DPR. Maka, calon hakim agung tidak mungkin dapat menjadi hakim agung, jika saja hasil seleksi yang sebelumnya dilakukan oleh KY, ternyata setelah diadakan fit and proper test ternyata DPR tidak menyetujuinya. DPR juga memberikan persetujuan terhadap Presiden tentang pengangkatan maupun pemberhentian anggota KY (Pasal 24B ayat (3) UUD 1945). Hal
I Gusti Ngurah Santika, SPd
314
mana tentunya dengan adanya persetujuan baik dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota KY oleh DPR, maka diharapkan dalam melaksanakan tugasnya kelak, KY dapat menjadi lebih independen, karena dalam proses pengangkatannya melibatkan dua lembaga negara, yaitu Presiden dengan persetujuan DPR. Ditambah lagi dikarenakan anggota KY tidak dapat diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR. selain itu, DPR mengajukan tiga orang untuk menjadi hakim konstitusi (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945). Tugas-tugas DPR sebagaimana dimaksudkan di atas adalah dalam rangka menjalankan mekanisme check and balances. Tentunya pendapat tersebut dalam hal ini adalah sesuai sekali dengan adanya ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan (2) UU No. 27 Tahun 2009, yang pada dasarnya telah menegaskan kembali prinsip-prinsip keseimbangan antara DPR dalam hubungannya dengan lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Seperti apa yang tercantum kemudian dalam ketentuan pasal tersebut di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa. a. DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna. b. DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna (kursif penulis). 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada era reformasi setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945, kemudian sistem ketatanegaraan Indonesia berubah secara mendasar, baik yang berkenaan dengan hubungan, kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan antara lembaga-lembaga negara. Termasuk juga adanya penambahan materi-materi yang selama ini belum dikenal dalam UUD 1945. Selain perubahan dan penambahan butir-butir ketentuan tersebut, perubahan UUD 1945 juga mengakibatkan adanya perubahan kedudukan dan hubungan beberapa lembaga negara, penghapusan lembaga negara tertentu, dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru (Eddyono,2010;5). Jika kita simak kembali hasil daripada Perubahan UUD 1945, ternyata sejak saat itu telah terjadi pula perubahan kelembagaan negara, seperti tidak lagi dikenal lembaga negara tertinggi, yang selama ini merupakan gelar bagi MPR bahkan dinyatakan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian, hubungan kelembagaan negara yang selama ini dipahami bersifat vertical hierarkis, berubah menjadi horizontal dengan mekanisme yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Selain itu, adanya ketentuan yang mengatur kelembagaan negara dalam UUD
I Gusti Ngurah Santika, SPd
315
1945 sebelum diamandemen, ternyata setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945 kemudian dihapus, seperti DPA. DPA menurut para perubah UUD 1945 tidak dipandang perlu kedudukannya sebagai suatu lembaga negara, yang kedudukannya terlepas dengan lembaga kepresidenan yang diberikan nasehat olehnya. Bahkan, bersamaan dengan hal tersebut di atas ternyata UUD 1945 kemudian memberikan kesempatan bagi pembentukan lembaga baru, dapatlah diketahui adanya lembaga yang baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Selain itu juga dibentuk sebuah lembaga negara yang bernama Dewan Perwakilan Daerah yang nantinya akan mewakili kepentingan daerah, dikancah nasional. Apabila kemudian dilihat kembali ke belakang, setidaknya ada empat gagasan fundamental berkaitan dengan proses amandemen di atas, yaitu pertama, anutan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan segala implikasinya sebagai ganti dari prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Kedua, diterapkannya kebijakan nasional yang menyangkut otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ketiga, gagasan pemilihan Presiden secara langsung, dan Keempat, gagasan pembentukan DPD yang akan melengkapi keberadaan DPR selama ini (Asshiddiqie dalam Aritonang,2009;2). DPD adalah lembaga baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang diangkat sebagai anggota MPR dan keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ragawino,2004;16). Dengan demikian, UUD 1945 telah memberikan kesempatan kepada rakyat-rakyat di daerah, untuk kemudian memajukan aspirasi lewat wakilnya berada di pusat, agar selanjutnya diperhatikan kepentingannya, yang tentunya disadari bahwa kepentingan daerah tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional. Oleh karena itu, daerah dapat pula berpartisipasi dalam tingkatan yang lebih luas, yaitu di pusat dengan menempatkan wakilwakilnya, yang akan berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya, agar kemudian dijadikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan oleh pusat yang akan berimplikasi luas terhadap rakyat di daerah. Dengan adanya perwakilan dari daerah di pusat, nantinya diharapkan ke depannya, pusat lebih memperhatikan aspirasi, yang berkaitan dengan kepentingan rakyat di daerah. Hal mana tentunya juga bertujuan untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat terutama berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maka perlulah kemudian diwujudkan lembaga melalui permusyawaratan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang diharapkan mampu mengejewantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah agar sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut
I Gusti Ngurah Santika, SPd
316
membuktikan bahwa daerah memiliki posisi yang penting dalam mempengaruhi keputusan dari pusat, agar tidak merugikan rakyat di daerah nantinya apabila kebijakan tersebut sudah dilaksanakan. Untuk itulah keberadaan DPD RI dalam desain bangunan ketatanegaraaan Indonesia dimaksudkan untuk menjembatani aspirasi lokal kedaerahan dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, kepentingan dan aspirasi lokal dapat terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pusat (Marzuki,2008;82). Dengan luasnya wilayah Indonesia apalagi daerahnya terpisah oleh lautan, menyebabkan kesulitan dalam komunikasi dengan pusat, termasuk juga dalam hal menyampaikan berbagai aspirasi yang ada di daerah, yang sebetulnya perlu diberikan kesempatan, bahkan dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebuah kebijakan nasional, maka untuk itulah diperlukan sebuah wadah berupa suatu lembaga negara yang dapat menampung aspirasi daerah pada tingkat pusat. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pusat tidak dapat dilepaskan dari daerah, utamanya dalam mengambil segala keputusan yang bersifat mengatur dan mengikat, yang kemudian tentunya secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap rakyat daerah-daerah, karena daerah juga menjadi bagian dari NKRI sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, pusat tidak dapat menerapkan suatu kebijakan bersifat sepihak yang sebenarnya berdampak luas, termasuk kebijakan yang secara tidak langsung mengenai rakyat di daerah, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari daerah tersebut, melalui wakil-wakilnya yang ada di pusat. Naja (2004;16) menyatakan bahwa DPD adalah merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah (ruang) yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan daerah dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional. Dengan demikian, setidaknya DPD sebagai wakil rakyat daerah di pusat diharapkan memiliki bargaining position dalam memperjuangkan berbagai aspirasi rakyat di daerah dalam bentuk kebijakan-kebijakan nasional yang tentu sifatnya menguntungkan. Untuk sekarang, sudah saatnya pemerintahan pusat tidak bisa lagi hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa melibatkan daerah dalam pengelolaan negara, karena daerah sendiri merupakan bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga wajib hukumnya apabila daerah diberikan pula kesempatan yang sama untuk menyatakan kehendaknya melalui wakil-wakilnya yang berada di pusat. Bahwa sebelumnya daerah tidak mendapatkan perhatian yang cukup oleh pemerintah pusat, bahkan daerah terkesan dipinggirkan tanpa menghiraukan aspirasinya. Daerah tidak pernah mendapat kesempatan untuk berkembang secara dinamis dan demokratis, semua serba ditentukan oleh pusat. Pemerintah pusat seolah-olah bertindak sebagai atasan bagi daerah, dan yang paling mengerti apa kebutuhan daerah (Huda,2008;132-133). Apa yang telah dinyatakan oleh Huda sangat tepat, untuk menggambarkan terkait dengan situasi dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
317
kondisi kehidupan daerah pada saat Orde Lama dan Orde Baru berkuasa. Pemerintah tidak pernah memberikan keleluasaan apapun kepada daerah untuk mencoba mengatur dirinya sendiri. Bahkan, semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah kemudian disedot habis oleh pusat, namun tak ada yang kemudian bisa dilakukan oleh daerah untuk menentang ketidakadilan tersebut, karena memang tak ada jalur yang disediakan oleh pusat untuk memperjuangkan nasib rakyat yang ada di daerah. Ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya kian lama ternyata bertambah mencolok mata, baik itu dalam bidang pembangunan infrastruktur. Bahkan pada waktu itu tidak jarang daerah yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pusat kemudian melakukan suatu perlawanan, dengan mengangkat senjata untuk berusaha memisahkan diri dari NKRI. Tampak terlihat pada waktu itu, pusat yang dalam hal ini adalah pemerintah telah menutup mata dan menutup telinga rapat-rapat terkait dengan aspirasi daerah dalam menuntut otnomi, yang dinyatakan dan terlihat dalam berbagai bentuk perjuangan bahkan sampai tindakan anarkis. Namun, tuntutan aspirasi yang demikian malah membuat pusat menjadi gelap mata, bahkan sebaliknya ditanggapi dengan kekerasan berupa kekuatan senjata, yang padahal waktu itu sebenarnya hanyalah untuk menutupi ketidakmampuan pusat dalam mengatur daerah, terutama dalam menyejahterakan rakyatnya di daerah. Tentunya, dengan berbagai pengalaman pahit di masa lalu, yang kemudian berwujud dengan berbagai bentuk tindakan rakyat di daerah, terutama untuk mewujudkan aspirasinya, yang sebelumnya tidaklah mendapatkan tempat yang, maka perlulah diperhatikan untuk sekarang ini. Diperlukan sebuah wadah yang mampu mewakili kepentingan daerah dalam menyampaikan aspirasinya pada tingkat pusat, terutama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah, baik dalam bentuk pemerataan pembangunan yang bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lannya sehingga menimbulkan kecemburuan sosial kemudian. Untuk itu, diharapkan kehadiran perwakilan daerah di pusat merupakan suatu solusi dalam memecahkan masalah yang dari awal kemerdekaan sampai saat ini belum juga dapat diselesaikan. Dengan adanya DPD, banyak keuntungan yang kemudian akan diperoleh, menurut Gerungan (2011;15) bahwa di samping itu juga mendorong lebih cepat berlangsungnya pembangunan dan terwujudnya kemajuan daerah-daerah. Terakhir keberadaan DPD untuk memperkuat ikatan daerahdaerah dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia. Dasar pemikiran tersebut di atas, karena setidaknya daerahlah sendiri yang paling memahami kondisinya, sehingga apa yang menjadi kebutuhannya yang perlu dipenuhi melalui pembangunan akan dapat diusahakannya terlebih dahulu secara mandiri, tanpa kemudian harus menggantungkan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
318
nasibnya kepada pusat. Jika memang seandainya daerah kemudian ternyata tidaklah mampu untuk mengelola urusannya sendiri, maka pusat dalam hal ini dapat cepat bertindak, agar tidak terdapat jarak terlalu jauh terkait dengan pembangunan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dengan demikian, diharapkan antara daerah yang satu dengan lainnya tidak terjadi ketimpangan sosial mencolok, yang mungkin akan berimbas kemudian terhadap persatuan dan kesatuan nasional, tidak lain disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial. Tujuan inilah yang mungkin dimaksudkan dalam rangka untuk memperkuat ikatanikatan dalam bingkai negara kesatuan. Tentunya perlu disadari bahwa rakyat di daerah perlu untuk menyampaikan aspirasinya tersebut kepada wakil dari daerahnya yang ada di pusat, agar selanjutnya diperjuangkan sehingga mampu menjadi sebuah kebijakan nasional, yang dapat memberikan keuntungan nyata bagi daerahnya tersebut. Asshiddiqie (2009;271) menyatakan bahwa kelahiran DPD sebagai instrumen untuk menetralisir arus disintegrasi yang dikhawatirkan banyak pihak. DPD diharapkan dapat menjadi wahana bagi kepentingan daerah untuk itu menentukan kebijakan nasional yang berkaitan dengan masalah daerah sehingga tidak ada lagi tuntutan pemisahan diri karena ketidakadilan yang dirasakan daerah tertentu. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan terkait dengan dimaksudkannya keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dalam UUD 1945, yaitu bertujuan untuk. 1. Memperkuat ikatan-ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. 2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan negara dan daerah; 3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang (MPR,2011;135). Kelahiran DPD sangat didasari oleh keinginan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membatasi kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi dan jaminan keutuhan integrasi wilayah negara. Selain itu, pembentukan DPD juga untuk dimaksudkan dalam rangka mereformasi parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bicameral) yang nantinya terdiri dari DPR dan DPD. Sehingga, dengan begitu proses legislasi terdapat sistem
I Gusti Ngurah Santika, SPd
319
pengawasan ganda (double checks). Dalam hal ini, DPR merupakan reprensentasi politik (political representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip reprensentasi teritorial atau regional (regional representation). Dengan demikian maka DPD memiliki tugas berkaitan dengan pembentukan undang-undang dan tugas supervise atas pelaksanaan undang-undang mengenai materi tertentu (Ranggawidjaja,2009;30). Hal mana adalah sesuai sekali dengan gagasan awal reformasi konstitusi yang melahirkan DPD yang dilatar belakangi oleh beberapa gagasan. Pertama, gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar (bicameral system) (Yarni,2007;22-23). Dengan kata lain bahwa semangat yang sangat mengelora dibalik proses amandemen konstitusi di periode awal dekade 2000-an adalah demokratisasi khususnya untuk memperjelas format perwakilan politik (Santoso,2007;396). Menurut Ghafur (2007;396) bahwa gagasan awal direformasinya struktur MPR pada amandemen keempat UUD 1945 lebih disebabkan karena ketidakjelasan daripada struktur MPR itu sendiri. Adanya Utusan Golongan dan Utusan Daerah dianggap tidak jelas mewakili apa dan siapa. Dengan demikian, DPD dapat pula dipandang sebagai koreksi dan penyempurnaan utusan daerah di MPR menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan. Keikutsertaan daerah dalam Utusan Daerah di MPR sangat terbatas yaitu pada saat sidang-sidang MPR (Selama Orde Baru, hanya dua kali dalam lima tahun) (Satoto,2007;15). Ditambah lagi menurut Pamungkas (2011;187) bahwa ide Perwakilan ruang ini terbentuk untuk mengkompensasi kelemahan dalam perwakilan politik yang ada di DPR. Jelaslah bahwa hanya dengan DPR sebagai perwakilan rakyat dalam bidang politik, ternyata belumlah dapat memenuhi semua harapan yang diletakan pada pundaknya, utamanya dalam mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang ada jauh di daerah-daerah, padahal aspirasi yang sebelumnya disampaikan merupakan kebutuhan bersifat mendesak bagi daerah tersebut untuk segera diwujudkan oleh pusat kemudian. Untuk itu perlu ada suatu badan perwakilan yang benar-benar dapat memberikan harapan, kepada daerah khususnya rakyatnya, agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi tanpa menunggu perdebatan-perdebatan politik yang ujung-ujungnya hanya mengambil keuntungan dari rakyat. Hal tersebut biasanya sering dinisbatkan kepada lembaga perwakilan rakyat, dikarenakan menurut Budiardjo (2008;319) bahwa anggota-anggotanya mudah dipengaruhi oleh fluktuasi politik, karena dipilih langsung oleh rakyat. Diharapkan, nantinya DPD sebagai sebuah lembaga negara yang dibentuk di samping lembaga negara yang sudah ada, yakni DPR mampu untuk saling mengawasi dan mengimbangi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam pembentukan undang-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
320
undang tidak hanya menjadi monopoli daripada DPR, namun juga dimiliki oleh DPD sebagai badan yang sama-sama memiliki kewenangan tersebut. Diharapkan, nantinya dengan adanya ketentuan tersebut akan berimplikasi pula terhadap kualitas daripada hasil legislasi, yang kemudian tentunya ke depan akan lebih memperhatikan kepentingan rakyat daerah, utamanya pada tingkat nasional. Dengan kehadiran DPD di tengah-tengah sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana kepentingan nasional yang dulunya merupakan prioritas utama serta tidak dapat tidak, harus menjadi pertimbangan paling utama, bahkan tanpa memperhatikan sedikitpun kepentingan daerah, yang sebenarnya merupakan kaki serta menjadi dasar daripada kokoh dan tegaknya NKRI, untuk sekarang mungkin bisa lebih diperhatikan dengan lebih baik. Paling tidak untuk sekarang, pusat tentunya tidak dapat membentuk peraturan yang mengikat daerah, tanpa adanya terlebih dahulu pertimbangan dari daerah yang akan diaturnya kemudian. Namun, apabila dilihat dengan seksama berkaitan dengan keterlibatan DPD dalam membentuk undang-undang, maka Manan dalam Yuliandri (2011;87) menyatakan DPD bukanlah lembaga yang memiliki hak untuk membentuk undang-undang, dikarenakan bahwa Pertama DPD pada dasarnya tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kedua, DPD hanya berwenang merancang undang-undang tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Ketiga, DPD tidak mandiri dalam membentuk UU, karena adanya ikut membahas rancangan Undang-Undang, menunjukan bahwa DPR lah yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. Pernyataan dari Yuliandri dengan mengutip pendapat Bagir Manan merupakan pernyataan tepat untuk menggambarkan tugas DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang berada di pusat, tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab berat. Namun, disisi lain juga ditentukan bahwa DPD merupakan lembaga yang legitimasi tinggi, karena dipilih oleh rakyat secara langsung tetapi tanpa diberikan fungsi dan wewenang yang dipandang memadai dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung telah menyebabkan DPD menjadi badan, yang tidak lebih daripada pembantu DPR dalam hal-hal berkaitan dengan daerah, serta kewenangan lainnya yang telah ditentukan dalam ketentuan 22D UUD 1945. Namun, disini dapat diambil hikmahnya bahwa setidaknya dengan kehadiran DPD untuk menyuarakan kepentingan daerah yang perlu ditetapkan kembali dengan kebijakan nasional, sedikit tidaknya akan menjadi pertimbangan bagi DPR dalam memutuskannya kemudian. Walaupun, dengan nama pertimbangan yang tentunya tidaklah mengikat sama sekali bagi DPR secara hukum, untuk kemudian memperhatikan pertimbangan daripada DPD yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya tersebut.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
321
Sebenarnya, sudah lama rakyat menginginkan bahwa daerah memang perlu untuk dilibatkan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerah itu sendiri. Namun, ketika di bawah pemerintah Orde Baru dasar pemikiran tersebut sepertinya tidaklah mendapat perhatian serta tempat yang layak untuk diakomodasi. Setidaknya jika dilihat kembali di sepanjang sejarah perjalanan republik ini, khususnya berkaitan dengan kepentingan daerah, yang perlu diputuskan kembali secara nasional, telah banyak menimbulkan gejolak di daerah. Dikarenakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pusat ternyata memiliki implikasi luas terhadap rakyat di daerah, tetapi dalam kenyataannya aspirasi daerah terlupakan. Tampak kemudian di berbagai daerah terjadi tindakan-tindakan yang berkehendak mencoba untuk melepaskan diri dari NKRI dengan mendirikan negara merdeka, yang semua itu dilakukan, merupakan bentuk daripada kekecewaan daerah yang tidak terakomodasi di pusat. Dalam kenyataannya dengan peristiwa tersebut, belumlah kemudian dapat menyadarkan pusat, bahkan berakhir dengan tindakan agresif yang dilakukan pusat, sebagai bentuk pembalasan atas pembangkangan daerah dengan tujuan utamanya hanyalah sekedar membungkam daerah. Itu membuktikan bahwa dasar pemikiran untuk mendapatkan kebebasan bagi daerah untuk secara sadar mengatur dirinya sendiri, telah pula berkembang semenjak Indonesia mulai merdeka, bahkan sampai sekarang merupakan suatu masalah yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan secara tuntas oleh pusat. Perwujudan pemikiran itu berkembang dari periode ke periode. Tahun 1998, gerakan reformasi secara prinsip menemukan bentuknya yang mendasar melalui perubahan makna dan paradigma (Anshari dkk,2009;2). Untuk selanjutnya, perlu kembali dilihat hasil daripada amandemen terhadap UUD 1945, yang telah menambahkan sebuah lembaga baru yang bernama DPD, dengan harapan dapat memenuhi keinginan daerah sebagaimana dimaksudkan di atas. Dimasukannya lembaga DPD dalam UUD 1945 melalui amandemen ketiga, yang kemudian oleh perubah UUD 1945 memasukannya dalam ketentuan Bab VIIA, yang di dalamnya terdiri dari 2 Pasal disertai dengan beberapa ayat. Pengaturan yang dimaksud tadi adalah ketentuan Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 22C UUD 1945 yang di dalamnya terdiri dari 4 ayat, sedangkan untuk ketentuan Pasal 22D UUD 1945, ternyata juga terdiri dari 4 ayat. Untuk lebih jelasnya maka akan dikutipkan terlebih dahulu bunyi daripada ketentuan Pasal 22 C secara lengkap, yaitu. 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
322
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undangundang. Dengan demikian, pemilu merupakan sarana untuk menempatkan wakil-wakil rakyat untuk menduduki jabatan-jabatan negara, tidak terkecuali pula dengan keanggotaan DPD yang dipilih dan ditentukan secara langsung oleh rakyat Indonesia setiap lima tahun sekali (vide 22E ayat (2) UUD 1945). Selain lembaga-lembaga negara lainnya yang mengisyaratkan bahwa keanggotaannya adalah kemudian dipilih oleh rakyat melalui pemilu, maka DPD sebagai salah satu lembaga negara yang baru ternyata juga mensyaratkan agar anggota-anggotanya merupakan hasil daripada pemilihan umum. Untuk menjadi peserta pemilihan umum anggota DPD adalah perseorangan (Pasal 22E ayat (4) UUD 1945), yang tentunya akan sangat berbeda dengan peserta untuk menjadi anggota DPR, hal mana harus melalui partai politik sebagai pesertanya. Berkaitan dengan peserta perseorangan untuk menjadi anggota DPD dalam pemilu, dapatlah kemudian ditemui dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan (kursif penulis). Berbeda dengan keanggotaan DPR, bahwa DPD dipilih setiap provinsi, yang berarti daerah pemilihannya adalah provinsi (Pasal 31 UU No. 8 Tahun 2012), bahkan dalam ketentuan Pasal 227 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 telah menyatakan bahwa Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya (kursif penulis). Dengan begitu, DPD merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi rakyat daerah yang diwakilinya, atau dengan kata lain apabila kemudian seorang calon DPD terpilih, maka itu berarti bahwa dia telah mewakili daerah tersebut. Sedangkan untuk anggota DPR, merupakan mewakili rakyat pada tingkat nasional tanpa membedakan daerah pemilihannya dari mana anggota tersebut terpilih, sehingga untuk itu kemudian anggota DPR berdomisili di ibu kota Negara Republik Indonesia (Pasal 74 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009). Kemudian ditentukan pula bahwa mengenai jumlah anggota DPD yang setiap provinsi sama, dengan adanya ketentuan ini maka setiap daerah memiliki jumlah wakil-wakil yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
323
sama, tanpa membedakannya jumlah penduduk di setiap daerah seperti dalam pemilihan anggota DPR, hal mana anggota DPR terpilih tersebut adalah tergantung dari jumlah penduduk yang dipersyaratkan oleh undang-undang, terutama dari jumlah penduduk dari daerah tersebut. Maka untuk itu, keanggotaan DPD yang paling utama menjadi pertimbangan adalah daerah pemilihan. Hal tersebut adalah selaras dengan sistem pilihan umum yang digunakan adalah sistem distrik berwakil banyak, yaitu setiap daerah memiliki wakil lebih dari satu orang, bahkan untuk sekarang jumlah anggota dari daerah sebanyak 4 orang. Dalam sistem distrik, wilayah kesatuan adminsitratif negara dibagi atas sejumlah distrik pemilihan. Jumlah distrik pemilihan harus sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen (Ranadireksa,2009;175). Dapatlah dilihat kemudian terkait dengan jumlah anggota perwakilan setiap daerah untuk DPD telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2012, yang bunyinya. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat)(kursif penulis). Ketentuan tentang sistem pemilihan umum untuk anggota DPD adalah sistem distrik berwakil banyak, kemudian dapat pula kita temukan kembali dalam undang-undang tentang pelaksanaan pemilihan umum anggota DPD yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tepatnya pengaturan terkait dengan hal di atas dapatlah kemudian ditemukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012, yang bunyinya. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak (kursif penulis). Untuk lebih mengetahui terkait dengan sistem pemilihan umum yang menggunakan sistem distrik, maka perlulah juga untuk diketahui mengenai keuntungan dan kelemahannya. Maka untuk itu, dapatlah dilihat dibawah ini tabelnya terkait dengan hal tersebut di atas. Keuntungan Sistem Distrik Kelemahan Sistem Distrik 1. Sistem ini lebih mendorong ke arah 1. Sistem ini kurang memperhatikan integrasi partai-partai politik karena kepentingan partai-partai kecil dan kursi yang diprebutkan hanya satu. Hal golongan minoritas, apalagi jika ini akan mendorong partai-partai untuk golongan-golongan ini terpencar dalam menyisihkan perbedaan-perbedaan yang berbagai distrik.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
324
ada dan mengadakan kerjasama, sekurang-kurang menjelang pemilihan umum, antara lain melalui stembus accord. 2. Fragmentasi partai dan kecendrungan 2. Sistem ini kurang representatif dalam membentuk partai baru dapat arti bahwa partai yang calonnya kalah dibendung; malahan sistem ini bisa dalam suatu distrik kehilangan suara mendorong ke arah penyederhanaan yang telah mendukungnya. Hal ini partai secara alami dan tanpa paksaan. berarti bahwa ada sejumlah suara yang Maurice Duverger berpendapat bahwa tidak diperhitungkan sama sekali, atau dalam negara seperti Inggris dan terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai Amerika, sistem ini telah menunjang mengadu kekuatan, maka jumlah suara bertahannya sistem dwi partai. yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan. 3. Karena kecilnya distrik, maka wakil 3. Sistem distrik dianggap kurang efektif yang terpilih dapat dikenal oleh dalam masyarakat yang plural karena komunitasnya, sehingga hubungan terbagi dalam kelompok etnis, religius, dengan konstituen lebih erat. Dengan dan tribal, sehingga menimbulkan demikian si wakil akan lebih cenderung anggapan bahwa suatu kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasional yang terpadu secara ideologis distriknya. Lagipula kedudukannya dan etnis mungkin merupakan prasyarat terhadap pimpinan partai akan lebih bagi suksesnya sistem ini. independen, karena faktor penting dalam kemenangannya dan kemenangan partai. Sekalipun demikian, ia tidak lepas sama sekali dari disiplin partai, sebab dukungan serta fasilitas partai diperlukan baik untuk nominasi maupun kampanye. 4. Bagi partai besar sistem ini 5. Ada kemungkinan si wakil cenderung menguntungkan karena melalui untuk lebih memerhatikan kepentingan distortion effect dapat meraih suara dari distrik serta warga distriknya, daripada
I Gusti Ngurah Santika, SPd
325
pemilih-pemilih lain, sehingga kepentingan nasional. memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen. 6. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional 7. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan Budiardjo (2008) Dapatlah kemudian diketahui dalam ketentuan ayat (2) dari Pasal 22C UUD 1945 tersebut, yang dalam kenyataan membatasi jumlah anggota DPD, yakni tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah anggota DPR. Berkaitan dengan adanya pembatasan mengenai jumlah anggota DPD, yang dinyatakan tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR, juga dapat ditemukan kembali pengaturannya dalam ketentuan Pasal 227 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009. Berkaitan dengan sistem distrik yang digunakan untuk pemilihan umum terutama dalam memilih anggota DPD, maka ada beberapa keuntungan dan kerugiannya, seperti anggota yang terpilih merupakan orang dekat dengan konstituennya, karena memang telah dikenal baik di daerahnya. Pemilu dengan sistem distrik lebih murah penerapannya, bahkan jika yang ikut berkompetisi dalam sistem pemilihan umum ini adalah partai politik, maka tersebut akan dapat semakin mendorong partai politik untuk berkoalisi, sehingga secara alami menjadikan sistem pemilu ini sebagai alat untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya, DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 22C ayat (2) UUD 1945). Kemudian yang berkaitan dengan pengaturan lainnya tentang DPD akan diatur kembali dengan undang-undang yang dibentuk lebih lanjut oleh DPR dan Presiden. Tentunya, berkaitan pengaturan lebih lanjut tentang DPD, telah diserahkan kepada DPR dan Presiden sebagai lembaga yang berwenang untuk mengaturnya kembali dalam bentuk undangundang yang akan menjadi dasar bagi DPD dalam melaksankan tugasnya. Kemudian dalam UU No. 27 Tahun 2009, berkaitan dengan pengaturan DPD lebih lanjut, telah ditegaskan pula terkait dengan tugas dan wewenang DPD, yang nantinya akan dipaparkan kembali di samping juga memang telah ditentukan sebelumnya dalam UUD 1945. Dalam ketentuan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
326
Pasal 224 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 yang menyatakan tugas dan wewenang DPD yaitu. a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; b. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan i. ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya (kursif penulis).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
327
Kemudian berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Dewan Perwakilan Daerah, telah ditentukan pula dalam ketentuan Pasal 22D UUD 1945, yang di dalamnya terdiri dari 4 ayat, yaitu. (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang (kursif penulis). Berkaitan dengan tugasnya DPD hanya dapat mengajukan, ikut membahas serta memberikan pertimbangan, melakukan pengawasan serta menyampaikan pengawasan dalam kaitannya dengan undang-undang dalam bidang tertentu kepada DPR. Namun, untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan undang-undang, yang ada kaitannya dengan kewenangan DPD tersebut, ternyata hanya terletak di tangan DPR. Bahkan rancangan undang-undang yang sebelumnya telah disampaikan oleh DPD kepada DPR, kemudian jika disetujui akan menjadi rancangan undang-undang dari DPR untuk kemudian dibahas bersama dengan Presiden, sampai memperoleh persetujuan bersama agar dapat menjadi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
328
undang-undang. Dengan demikian, tentunya tidak sesuai dengan semangat yang melatar belakangi kelahiran lembaga negara tersebut, agar bisa dilibatkan dalam membentuk kebijakan di pusat, sehingga rakyat di daerah tidak dirugikan nantinya. Besarnya kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 antara DPD dan DPR adalah tidak sebanding, apalagi berkaitan dalam bidang pembentukan undang-undang, tentunya tidaklah mungkin dapat diterapkan mekanisme checks and balances yang sebelumnya menjadi tujuan utama diamandemennya UUD 1945. Karena hubungan yang bangun oleh UUD 1945 secara struktural telah menempatkan kedudukan DPD sebagai suboordinat daripada DPR, sehingga DPD tidak memiliki peran yang banyak dalam menentukan bidang pembentukan undang-undang. Walaupun undang-undang yang dibentuk kemudian, dalam kenyataannya jelas-jelas bersentuhan dengan kepentingan utama yang diwakilinya, yakni daerah. Adanya pengaturan tersebut memang sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) UndangUndang Dasar 1945, yang pada garis besarnya telah memberikan kekuasaan membentuk undang-undang hanya kepada DPR dan Presiden. Sedangkan keberadaan dalam forum tersebut, DPD hanya dapat ikut membahas dan memberikan pertimbangan, terkait dengan undang-undang tertentu, tanpa dapat untuk ikut serta guna mengambil keputusan yang menguntungkan baginya. Namun, patutlah untuk disyukuri, bahwa sedikit tidaknya dengan adanya pertimbangan dari DPD yang diberikan kepada DPR tentunya ke depannya memiliki sedikit pengaruh, terutama terhadap keputusan yang akan diambil oleh pembentuk undang-undang. Seperti yang telah disinggung di atas, pertimbangan DPD tentunya tidak memiliki sifat mengikat secara hukum, sehingga DPR sebagai membentuk undang-undang kemudian, tidak harus untuk mengikuti pertimbangan dari DPD. Jadi terkait dengan pertimbangan dari DPD tersebut, DPR pada dasarnya boleh ikut juga boleh tidak, sehingga dalam kenyataan terkait dengan pertimbangan yang diberikan oleh DPD adalah tergantung daripada kehendak DPR. Kemudian juga ditentukan dalam konstitusi bahwa walaupun DPD tidak memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, namun setelah adanya undang-undang yang berhubungan dengan kewenangan DPD tersebut, maka konstitusi telah menugaskan kepada DPD agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang yang bersinggungan dengan kewenangan DPD. Namun, untuk DPD dalam konstitusi ditentukan bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil suatu tindakan apapun, apabila suatu hari ternyata ada suatu tindakan yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersentuhan dengan kewenangan DPD tersebut, atau dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undangundang tersebut, maka DPD hanya bewenang untuk kemudian melaporkan pengawasan tersebut kepada DPR, dengan harapan akan diambil tindak lanjut kemudian oleh DPR.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
329
Kemudian selanjutnya terkait dengan laporan pengawasan dari DPD, DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan pengawasan dari DPD tersebut, dapat mengambil keputusan terkait dengan laporan tersebut, apakah akan ditindaklanjuti atau tidak proses lebih lanjut. Dengan demikian, secara sepintas terlihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada DPD oleh UUD 1945 sangat terbatas, bahkan terkait dengan masalah tersebut, kemudian dapatlah dikatakan bahwa semua berkaitan dengan kewenangan DPD merupakan perpanjangan tangan dari DPR. Menurut UUD 1945 ternyata DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR tentang APBN yang diajukan oleh Presiden (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945) kemudian DPR menerima dan menindaklanjutinya pertimbangan tertulis tersebut terhadap rancangan undang-undang tentang APBN (Pasal 154 ayat (1) UU No.27 Tahun 2009). Lebih lanjut terkait dengan adanya pertimbangan DPD tentang APBN kepada DPR tersebut, maka oleh UUD 1945 ternyata DPD dalam kedudukannya juga memberikan pertimbangan kepada DPR tentang pemilihan anggota BPK (Pasal 23F ayat (1) UUD 1945, ketentuan yang sama dapat ditemukan kembali dalam ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009, yaitu DPD memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai calon anggota BPK. Hanya inilah kewenangan tambahan dimiliki oleh DPD yang telah ditentukan dalam UndangUndang Dasar 1945. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa DPD hanya memiliki wewenang terbatas, hal mana tentunya sangat berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Bahkan, berkaitan dengan wewenang DPD dalam memberikan pertimbangan kepada DPR berhubung dengan pemilihan anggota BPK, sebenarnya bukanlah tugas yang penting bagi DPR untuk memperhatikan pertimbangan dari DPD. Hal ini karenakan bahwa ada atau tidaknya pertimbangan DPD tidaklah mempengaruhi dalam pemilihan anggota BPK, karena DPR akan tetap saja melaksanakan tugasnya untuk memilih anggota BPK meskipun tanpa adanya pertimbangan dari DPD (lihat ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009). Berikut ini, merupakan ringkasan tabel dari kewenangan DPD yang terdapat dalam UUD 1945. Untuk lebih memperjelas mengenai tugas-tugas daripada Dewan Perwakilan Daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu untuk menunjukan sebuah tabel, sehingga dengan demikian diharapkan tabel tersebut dapat memberikan gambaran jelas, apa yang sebenarnya menjadi kewenangan DPD secara konstitusional. Namun, tabel tersebut merupakan pengolahan daripada tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hanya hal-hal pokok saja yang ditulis dalam tabel. Tabel 2.2
I Gusti Ngurah Santika, SPd
330
Kewenangan DPD dalam UUD 1945
RUU dalam bidang 1. Otonomi Daerah.
Kewenangan DPD
Dapat mengajukan, ikut membahas, dapat mengawasi. Dapat mengajukan, ikut membahas, 2. Hubungan Pusat dan Daerah. dapat mengawasi. 3. Pembentukan dan Pemekaran Dapat mengajukan, ikut membahas, dapat mengawasi. serta penggabungan Daerah. 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dapat mengajukan, ikut membahas, dan Sumber Daya Ekonomi dapat mengawasi. lainnya. 5. Perimbangan Keuangan Pusat dan Dapat mengajukan, ikut membahas, dapat mengawasi. Daerah. 6. Rancangan Anggaran Pendapatan Memberi pertimbangan atas mengawasi pelaksanaannya. dan Belanja Negara. Memberi pertimbangan atas 7. Pajak. mengawasi pelaksanaannya. Memberi pertimbangan atas 8. Pendidikan. mengawasi pelaksanaannya. Memberi pertimbangan atas 9. Agama. mengawasi pelaksanaannya. 10. Pemilihan Anggota BPK (bukan Memberi pertimbangan. dalam pembuatan RUUnya). RUU, RUU, RUU, RUU,
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi sistem sosial, politik, dan ekonomi guna mewujudkan demokrasi telah mengubah sistem dan struktur pemerintahan Indonesia. Sementara itu, tuntutan untuk mengikis KKN memerlukan peningkatan dalam transparansi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
331
fiskal atau pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan negara. Berdasarkan keinginan dan aspirasi dari berbagai unsur rakyat Indonesia yang telah mengkristal dan jelas tersebut, tujuan nasional untuk segera dihapuskannya praktek-praktek korupsi harus segera dicapai (BPKP,1999;32). Dikarenakan selama ini, negara telah banyak dirugikan oleh praktek-praktek korupsi yang telah menyengsarakan rakyat, terutama dilakukan oleh para pejabat negara yang seharusnya menjadi teladan agar bisa diikuti kemudian oleh rakyat. Berkaitan dengan keuangan negara merupakan masalah yang sifanya sangat mendasar dalam bidang kenegaraan, karena uang merupakan salah satu sumber kekuasaan, sehingga tentunya memiliki kedudukan yang penting, ternyata dimanfaatkan oleh oknumoknum pejabat tertentu untuk mendapatkan uang dengan menguras negara. Memang dalam sejarah perjalanannya republik Indonesia, terbukti sangat sulit untuk melakukan pengelolaan keuangan negara yang bersih, transfaran dan akuntabel, kemudian tentu pada akhirnya, mampu memberikan keuntungan bagi rakyat luas, namun malahan yang terjadi adalah kian menjamurnya praktek korupsi disegala lini kehidupan. Bahkan, keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata tidak luput daripada incaran para koruptor dalam rangka memperkaya dirinya, dengan menutup mata atas tindakannya yang bersifat melanggar hukum, sehingga keuangan negara dirugikan. Namun, sampai akhir kekuasaan Orde Baru pun ternyata berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan mampu bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan negara, memang masih sangat sulit untuk dilaksanakan. Hal mana dikarenakan, menurut Rajagukguk (2006;4) bahwa bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas kemudian dapat dikelompokkan kembali ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan luasnya pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksudkan oleh Rajagukguk, merupakan suatu tantangan tersendiri, bahkan menjadi tuntutan utama ke depannya, bagaimana caranya para penyelenggara negara untuk mewujudkan sebuah keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Sehingga, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi keuangan negara, benar-benar dapat diwujudkan oleh para penyelenggara negara. Mungkin yang menjadi tujuan utama tersebut di atas, adalah berkaitan dengan mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi fiskal merupakan komponen utama dari upaya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
332
penciptaan clean government dan good governance. Sebelumnya memang ada lembagalembaga negara yang juga bertugas, untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, namun dalam kenyataannya belum mampu memenuhi tujuan sebagaimana diharapkan. Bahkan tidak jarang terindikasi bahwa lembaga yang memiliki kemandirian dan kebebasan tersebut, ternyata dalam tugas dan wewenangnya untuk menjaga agar pemerintahan tetap bersih, tetapi tidak dapat berbuat banyak terutama dalam membatasi penyelewengan di bidang pengelolaan keuangan negara. Bahwa untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang benar-benar bebas, mandiri, dan profesional untuk mampu menciptakan pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, selain adanya lembaga-lembaga negara lainnya yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. Maka negara Indonesia untuk sekarang masih memiliki Badan Pemeriksaan Keuangan yang ditentukan betugas untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi dasar manajemen adalah mutlak dalam penyelenggaraan menajemen negara atau administrasi negara (Sujamo,1994;75-76). Tanpa pengawasan yang baik, tentunya potensi untuk terjadinya penyelewengan kekuasaan adalah sangat besar, bahkan hal tersebut pasti akan terjadi di dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat saja kemudian menyebabkan negara seringkali dirugikan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab yang kebetulan ketika itu bertugas sebagai memegang ataupun mengurus keuangan negara. Bergulirnya era reformasi, yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenannya membawa angin segar dalam kaitannya pengelolaan keuangan negara. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan menempatkan kembali BPK berdasarkan fungsi yang sebenarnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri negara. Pada waktu Orde Baru berkuasa telah melulu lantahkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, yang tentunya berakibat dirugikannya uang rakyat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, bahkan tidak ada yang dapat mengawasi apalagi sampai meminta pertangungjawabannya secara hukum. Walaupun sebelum runtuhnya kekuasaan dari Orde Baru telah ada sebuah lembaga negara yang bernama BPKP, namun nampaknya belum dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang seharusnya. Sebelum lebih lanjut membahas terkait dengan BPK, maka ada baiknya kita kembali
I Gusti Ngurah Santika, SPd
333
menelusuri sejarah ke belakang terutama untuk lebih memahami tentang keberadaan lembaga BPK tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK sendiri berdiri sejak tahun 1947, dalam perjalanannya secara panjang dalam melaksanakankan tugas dan kewenangan walaupun serba kekurangan yang menyertainya. Hal ini dikarenakan pada waktu itu adalah masa revolusi fisik yang tentunya menguras tenaga, namun tidak mengurangi apresiasi kita terhadap lembaga ini dalam menjalankan tugas dan perannya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Pada era Hindia Belanda, lembaga dengan tugas seperti yang diemban BPK sekarang bernama "Algemeene Rekenkamer" (ARK). Lembaga ini ditopang peraturan perundangan yang lengkap, antara lain Indische Comptabiliteits Wet(ICW) dan Instructie en verdure bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR). Namun, sejak menjadi sebuah lembaga tinggi negara dan namanya menjadi "Badan Pemeriksa Keuangan", instansi ini tak kunjung memiliki pijakan peraturan pelaksanaan yang memadai. Padahal jika lihat kembali Penjelasan UUD 1945 sebelum dicabut, dinyatakan secara tegas bahwa sebenarnya BPK memiliki tugas yang sangat berat yang dibebankan oleh UUD 1945. Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi. Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintah. Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang. Namun, dalam kaitannya ini dapatlah dilihat dalam perjalanannya pada masa pemerintahan Orde Baru, berkaitan dengan BPK dapat dikatakan telah mereduksi tugas dan perannya yang telah dimanatkan oleh UUD 1945. Padahal jika lihat dari Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan sebagaimana dimaksud di atas, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, maka sebenarnya BPK memiliki fungsi yang strategis. Dengan kedudukan sepenting itu, faktanya hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun1973, BPK hanya memiliki pijakan satu ayat dari Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ayat (5). Dan, undang-undang yang dibuat itu pun sejatinya hanya adopsi belaka dari peraturan-peraturan peninggalan era kolonial yang tak sesuai dengan semangat Pasal 23 UUD 1945. Tentu bisa dimengerti mengapa begitu "minim" pijakan BPK dalam UUD 1945. Untuk lebih jelasnya, maka akan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
334
dikutipkan bunyi ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 sebelum perubahan, yang bunyinya. (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (kursif penulis). Undang-undang sebagaimana dimaksud di atas ( UU No. 5 Tahun 1973) yang mendasari BPK masih terbatas pada hal-hal yang pokok saja, mulai dari kewajiban, hak, wewenang, hubungan kerja, dan kedudukannya dalam berhadapan dengan legislatif maupun eksekutif. Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan pelaksanaan, sebagian masih didasarkan pada peraturan lama, dan penerapannya tidak mendukung apa yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga dengan kedudukan yang mandiri, lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dengan bekal yang serba terbatas seperti itu, dalam praktik sering terjadi kondisi-kondisi yang tidak mencerminkan kemandirian BPK. Pada saat Orde Baru, Ketua BPK ditunjuk oleh Presiden dan seterusnya. Akibatnya, hasil-hasil kerja keras BPK menjadi seakan-akan tidak memiliki nilai atau daya yang semestinya. Selain itu, baik secara samar-samar maupun terang-terangan, kedudukan dan peran BPK tereduksi karena adanya pembatasan obyek, metode dan laporan audit, pengontrolan anggaran dan SDM oleh pemerintah secara ketat, dan adanya lembaga-lembaga pengawas yang juga melakukan fungsi-fungsi pemeriksa, seperti BPKP, Irjen-Irjen, Itwilprop dan lain-lain. Ini sesungguhnya tidak hanya mereduksi kedudukan dan hak konstitusional BPK, tetapi pada akhirnya juga mengganggu kinerja lembaga-lembaga yang diaudit (anonim) Dengan demikian, seharusnya dalam menggunakan keuangan negara harus digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu diperlukan pertanggungjawaban jelas yang seharusnya diberikan oleh lembaga/badan yang mana sebelumnya menggunakan keuangan negara tersebut. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tidak lain, wewujudkan kehidupan yang bersih dimulai dari pengelolaan keuangan negara, merupakan tuntutan reformasi dalam memulai kehidupan demokrasi setelah jatuhnya pemerintahan korup. Tak pelak, demokrasi pun membawa serta tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Di sinilah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
335
BPK menemukan jalan untuk meraih kembali kedudukan dan perannya yang sejati. Pijakan BPK dalam menjalankan tugas konstitusionalnya menjadi semakin kokoh setelah adanya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang memaklumkan pemulihan independensi BPK Oleh karena itu, untuk memeriksa pertanggungjawaban terkait dengan keuangan negara, telah diamanatkan oleh UUD1945 kepada sebuah lembaga negara, yaitu BPK. Kemudian setelah diamandemennya UUD 1945 ketentuan BPK juga mengalami perubahan cukup mendasar, maka perubahan yang dialami oleh BPK akan dibahas selanjutnya di bawah ini. Untuk itulah kemudian akan dikutipkan kembali secara keseluruhan ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi BPK dalam UUD 1945. Kemudian untuk selanjutnya akan dibahas ketentuan pasal-perpasal seperlunya, sehingga yang menjadi harapan ke depannya adalah pembaca dapat lebih memahaminya dengan lebih baik. Dalam Bab VIIIA yang di dalam terdiri dari 3 Pasal, yang selanjutnya akan dipaparkan sebagai berikut. Pasal 23E 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang (kursif penulis). Dalam ketentuan Pasal 23E ayat (1) dinyatakan bahwa BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Bebas dan mandiri yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Sehingga, BPK dalam menjalankan kewenangannya tidaklah kemudian dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun maupun dalam bentuk apapun. Kebebasan dan kemandirian BPK dalam menjalankan tugasnya merupakan jaminan bagi terselenggaranya pemerintahan yang bebas dan bersih dari segala praktek korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan demikian, penulis memahami bahwa tidak hanya lembaga negara yang menggunakan keuangan negara saja yang harus bertanggung jawab, namun tentunya dalam hal ini BPK sendiri sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara, tentu seharusnya ikut pula secara langsung bertanggungjawab, bahkan bertugas sebagai penanggungjawab utama untuk menjaga agar
I Gusti Ngurah Santika, SPd
336
keuangan negara dikemudian hari tidak dirugikan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab, yang kebetulan pada waktu itu sedang menduduki jabatan serta dipercayakan untuk mengurus keuangan negara. Hal inipun dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) UU No. 15 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (kursif penulis). Sedangkan berkaitan dengan kebebasan dan kemandirian BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, pada dasarnya menyatakan bahwa. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun oleh the founding fathers kita menugaskan BPK sebagai satu-satunya auditor yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berbeda dengan di banyak negara lain, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan BPK sejajar dengan lembagalembaga negara yang ada dalam struktur negara kita. Di berbagai negara yang lain lembaga auditor eksternal seperti BPK ditempatkan langsung di bawah lembaga legislatif sebagai pemegang hak bujet. Lembaga legislatif itulah yang menugaskan auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Selain tetap mempertahankan pemberian hak eksklusif pemeriksaan keuangan negara kepada BPK, perubahan ketiga dari UUD 1945 justru telah memperkuat posisinya dengan memberikan kedudukan yang bebas dan mandiri" kepada BPK. Baik naskah asli maupun perubahan, UUD 1945 menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. ltulah sebabnya mengapa diberikan kedudukan tinggi, kebebasan dan kemandirian kepada BPK. Maksudnya adalah agar BPK dapat melaksanakan tugasnya secara objektif. BPK dapat memeriksa dan melaporkan keuangan negara sebagaimana adanya, bebas dari pengaruh maupun tekanan politik. Termasuk dari ketiga cabang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun judikatif (Anonim,2005;2). Selain adanya ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang kemudian juga menyatakan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri, selanjutnya dalam UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, khususnya berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 undang-undang tersebut, menyatakan bahwa : BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung
I Gusti Ngurah Santika, SPd
337
jawab keuangan negara (kursif penulis). Bahkan, dalam UU No. 15 Tahun 2006, objek yang diperiksa oleh BPK berkaitan dengan keuangan negara adalah sangat luas, hal mana kemudian dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (kursif penulis). Dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 berkaitan dengan lembaga atau badan lainnya dijelaskan bahwa : yang dimaksud dengan lembaga atau badan lain antara lain: badan hukum milik negara, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang, dan badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara (kursif penulis). Ketentuan tersebut adalah sesuai pula dengan pendapat yang diberikan oleh Nasution (2007;1) bahwa UUD 1945 memberikan posisi yang sangat tinggi pada BPK sebagai suatu lembaga negara sendiri. Tugas BPK adalah untuk memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara. BPK bertugas untuk memeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. BPK bertugas untuk memeriksa dimana uang negara itu disimpan. BPK sekaligus bertugas untuk memeriksa untuk apa uang negara tersebut dipergunakan. Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut bahwa keuangan negara di Indonesia bukan saja tercermin pada APBN dan APBD. Keuangan negara itu juga tercermin pada kegiatan BUMN dan BUMD, yayasan, dana pensiun maupun perusahaan yang terkait dengan kedinasan. Bahkan, keuangan negara juga mencakup bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta. Dengan demikian, dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan objek yang akan diperiksa kemudian oleh BPK adalah luas sekali, pembatasannya adalah hanya pada lembaga/badan yang tidak menerima dan/atau mengelola keuangan negara, bukanlah merupakan objek dari BPK dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan pengawasan pengelolaannya di bidang keuangan negara. Sehingga, yang menjadi kesimpulan di sini adalah, baik apakah itu badan maupun lembaga adalah pada dasarnya memiliki pertanggungjawaban terhadap keuangan negara, asalkan lembaga atau badan tersebut telah menerima dan/atau mengelola keuangan negara. Dalam melakukan tugasnya BPK berkaitan dengan pengawasan terhadap keuangan negara tersebut, maka Widjaja (2002;9)
I Gusti Ngurah Santika, SPd
338
memberikan pengertian, apakah yang selanjutnya dimaksud dengan keuangan negara, yang menurutnya pendapatnya bahwa. Dengan Keuangan Negara tidak hanya dimaksud uang negara, tetapi seluruh kekayaaan negara, termasuk di dalamnya segala bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya baik kekayaan itu berada dalam pengurusan pada pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, yayasanyayasan pemerintah, dengan status hukum publik maupun hukum perdata, perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan di mana pemerintah mempunyai kepentingan khusus dalam pengusahaan dan pegurusan pihak lain maupun berdasarkan perjanjian dan penyertaan (partisipasi) pemerintah ataupun penunjukan dari pemerintah. Dengan paparan singkat sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas, yang telah menggambarkan pentingnya peran BPK dalam era reformasi, dimana dituntut untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa utamanya dalam pengelolaan keuangan negara. Bahkan, seperti apa yang selanjutnya digambarkan oleh Edstrom (2009;7) bahwa secara singkat, tantangan reformasi pengelolaan keuangan tersebut di atas mempunyai implikasi perubahan paradigma sistem pemerintahan yang telah menuntut Pemerintah Indonesia untuk segera menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, BPK diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakilnya. Oleh karena itu, setiap pengelolaan keuangan haruslah dilakukan sesuai dengan aturan benar, dan untuk menjamin hal tersebut diperlukan mekanisme pemeriksaan yang kemudian disebut financial audit. Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan semacam itu memerlukan lembaga negara tersendiri, yang mana dalam bekerjanya bersifat otonom atau independen. Independensi tersebut sangat penting, karena dalam menjalankan tugasnya, pejabat pemeriksa tidak boleh diintervensi oleh kepentingan pihak yang diperiksa atau pihak lain yang mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung, sehingga mempengaruhi obyektifitas pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggungjawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjungjung tinggi integritas, objektifitas, dan independensi (Saidi,2008;60). Badan Pemeriksa Keuangan adalah suatu badan yang tugasnya lebih banyak dititik beratkan kepada tindakan yang bersifat represif (Mezak,2009;100).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
339
Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, hanya dapat dilakukan kemudian, jika penggunaan keuangan negara telah dilakukan. Selaku lembaga negara, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kedudukan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wujud pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat. Sekalipun bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat tidak berarti bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berada di bawah Dewan Perwakilan Rakyat. Konstruksi kelembagaan menurut Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga negara yang berfungsi melaksanakan kedaulatan rakyat (Saidi,2011;83). Sehingga diantara kedua lembaga negara tersebut tidak ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi, namun hanya berkaitan dengan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945. Kemudian jika lihat kembali seperti apa yang kemudian dicantumkan dalam UUD 1945, berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dari BPK, di mana nantinya hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kembali kepada DPR. Dapatlah kemudian BPK dikatakan merupakan salah satu perpanjangan tangan DPR dalam melakukan fungsi pengawasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di bidang pengawasan dan penganggaran sampai legislasi. Bahwa dari pembahasan tersebut di atas, BPK sesungguh dapat dikatakan lebih dekat fungsinya dengan ranah kekuasaan daripada legislatif atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan kekuasaan legislatif, tidak lain dikarenakan bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu, dapatlah kemudian dilihat kembali dalam ketentuan Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya (kursif penulis). Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, Asshiddiqie (2009;198) kemudian menyatakan bahwa lembaga legislatif tersebut, khususnya DPRsebagai pengawas di bidang politik, dibantu pula oleh lembaga pengawas keuangan yang dinamakan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu, fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) haruslah dilihat keterkaitannya dengan penyelenggaraan fungsi pengawasan atau fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Pendapat bernada sama dijuga dipaparkan oleh Thalhah dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
340
Malian (2011;80) dengan menyatakan bahwa fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan lembaga ini sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi pengawasan oleh parlemen. Karena itu, kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif, atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, dapatlah kemudian kita temui kembali dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa : BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya (kursif penulis). Kemudian, dari adanya laporan tersebut, yang pada dasarnya merupakan hasil daripada pemeriksaan BPK, berdasarkan laporan tersebut selanjutnya akan ditindak lanjuti kembali oleh lembaga perwakilan dan/atau badan yang sesuai dengan undang-undang. DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjutinya pemeriksaan tersebut berdasarkan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan tersebut (Pasal 7 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006). Maksudnya di sini adalah DPR dapat saja menindaklanjuti dengan mengadakan tindakan pengawasan, seperti ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 atau menindaklanjuti dengan tidak mengadakan pengawasan, karena memang tidak ditemukan adanya tindakan yang merugikan keuangan negara. Pada dasar tindak lanjut yang nantinya dilakukan oleh DPR tentunya berhubungan erat dengan ketiga fungsinya seperti apa yang tercantum dalam UUD 1945. Selain itu, kata badan artinya dapat saja BPK melaporkan kepada badan-badan penegak hukum, jika diindikasikan ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum, tentunya tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang telah merugikan keuangan negara, hal mana adalah sangat tergantung daripada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah tersebut. Berkesesuaian dengan pendapat tersebut, ternyata Rai (2008;6) juga menyatakan bahwa di samping itu, apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana atau kerugian negara, maka BPK wajib melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan kepada aparat hukum akan dilakukan hanya Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini dalam UUD 1945, diharapkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan dapat meningkatkan tranparansi dan tanggungjawab (akuntabilitas) keuangan negara (Huda,2011;210).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
341
Dari tugas dan wewenang tersebut di atas, BPK dapat dikatakan memiliki tiga (3) fungsi pokok, yakni: 1. Fungsi operatif, yaitu melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. 2. Fungsi yudikatif, yaitu melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, serta menimbulkan kerugian negara. 3. Fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara (ICCE UIN,2010;76). Kemudian, lebih lanjut hal-hal yang berhubungan dengan BPK dalam UUD 1945, terutama yang mengatur tentang keanggotaan BPK serta tata cara pemilihan pimpinan BPK telah pula ditentukan dalam ketentuan Pasal 23F UUD 1945 yang berbunyi. 1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota (kursif penulis.) Berkaitan dengan tata cara pengisian keanggotaan BPK, yang ditentukan kemudian untuk dipilih oleh DPR. Ternyata dalam UU No. 15 Tahun 2006 tidaklah temukan maksud terkait dengan kata dipilih, namun dalam ketentuan Pasal 170 UU No. 27 Tahun 2009 terdapat kalimat yang menyatakan bahwa DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD (kursif penulis). Kemudian, dalam Penjelasannya dinyatakan cukup jelas, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kata dipilih dalam ketentuan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945, maupun kata memilih dalam ketentuan Pasal 170 UU No. 27 Tahun 2009. Dengan demikian, berkaitan dengan kata memilih maupun dipilih penulis dalam hal ini mengartikan, jika misalnya dalam pengisian keanggotaan BPK memerlukan 2 orang anggota, maka dalam hal ini bisa saja kemudian diadakan pengajuan calonnya ke DPR, dengan jumlah calonnya adalah lebih daripada jumlah yang memang dibutuhkan untuk pengisian keanggotaan BPK, sehingga DPR dapatlah memilih dengan leluasa. Namun, DPR dalam memilih keanggotaan BPK, dalam kenyataannya telah ditentukan untuk memperhatikan dan mendengar pertimbangan yang diberikan oleh DPD sebelum mengambil keputusan tentang pengangkatan keanggotaan BPK. Dengan adanya pertimbangan dari DPD, setidaknya untuk pemilihan anggota BPK, diharapkan lebih banyak masukan berupa kritik maupun saran yang kemudian akan diterima sebagai pertimbangan bagi DPR. Sehingga untuk ke depannya semakin memantapkan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
342
pertimbangan DPR dalam menentukan serta kemudian memutuskan siapakah yang berhak menjadi anggota BPK, sehingga kemudian keputusan untuk menggangkat anggota BPK tidak hanya berdasarkan pertimbangan politis semata. Namun, perlu untuk diketahui bahwa terkait dengan pertimbangan yang diberikan oleh DPD kepada DPR, tidaklah sifatnya mengikat bagi DPR dalam mengambil keputusan untuk memilih anggota BPK. Dengan begitu, anggota BPK yang telah ditentukan untuk dipilih oleh rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Kemudian dengan begitu dapat dikatakan bahwa BPK telah mendapatkan mandat dari rakyat sebagai salah satu pemegang kedaulatan rakyat, seperti apa yang diamanatkan oleh UUD 1945. Hal mana adalah sesuai dengan kedaulatan rakyat yang telah ditentukan berdasarkan hukum konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Dengan demikian, tentunya BPK khususnya mengenai anggota-anggotanya, tentunya memiliki legitimasi yang tinggi, terutama untuk menjalankan tugasnya, dikarenakan pengangkatannya dilakukan oleh rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat, yang kemudian tercermin dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, telah dijamin oleh konstitusi agar BPK bersifat merdeka dan independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, tentunya terkait dengan anggota BPK yang telah dipilih oleh DPR tidaklah dapat diberhentikan seenaknya, kecuali karena anggota BPK tersebut telah melakukan tindakan yang sifanya bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan kewajibannya dalam melakukan tugas-tugasnya dibidang pemeriksaan keuangan negara. Bahkan dalam pemberhentian maupun sanksi terhadap anggota BPK yang lalai dalam melakukan tugasnya, atau bertentangan dengan kewajibannya kemudian, ternyata telah ditentukan pula dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Selain hal tersebut di atas, berkaitan dengan keterlibatan DPR dalam pengangkatan BPK adalah bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap peningkatan peran dan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang bebas dan mandiri serta memiliki profesionalisme. Dengan demikian, pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Selanjutnya, anggota BPK yang sebelumnya sudah dipilih oleh DPR, kemudian melanjutkan kembali untuk memilih ketua BPK (Pasal 23F ayat (2) UUD 1945), yang berarti pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK berada di tangan anggota BPK itu sendiri. Dengan demikian, anggota BPK sendirilah yang mempunyai kewenangan dalam memilih Ketua dan Wakil Ketuanya, untuk selanjutnya diresmikan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi tertinggi yang memang telah ditentukan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
343
oleh UUD 1945. Dengan dasar pemikiran yang melandasi pengaturan tersebut dalam UUD 1945 tersebut, maka diharapkan ke depannya ada suatu kerjasama yang sifatnya baik antara anggota dan ketua dalam menjalankan tugasnya seperti yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Selanjutnya terkait dengan pengaturan BPK, juga diatur kembali dalam ketentuan Pasal 23G UUD 1945 mengenai kedudukan maupun perwakilannya serta berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut berkenaan BPK diatur kembali dengan undang-undang. Dalam ketentuan Pasal 23G UUD 1945 yang di dalamnya terdiri dari 2 ayat, menyatakan bahwa. 1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Peraturan yang sama dapat dilihat kemudian dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang dalam kenyataaan juga mengatur kedudukan BPK dan perwakilannya di setiap provinsi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. BPK berkedudukan di ibu kota negara, yang berarti BPK berkedudukan di Jakarta dan juga telah ditentukan untuk memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia, sehingga untuk BPK berarti harus ada di 33 provinsi seluruh Indonesia. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, tentunya akan disesuaikan kembali dengan kemampuan negara, khususnya berkaitan dengan keuangan negara untuk membentuk badan-badan perwakilannya di masing-masing provinsi. Pengaturan ini dapat dilihat kemudian dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa untuk pembentukan perwakilan BPK dimasingmasing provinsi ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, mengenai ketentuan BPK yang kemudian diatur kembali dengan bentuk undang-undang menurut ketentuan ayat (2) dari Pasal 23G UUD 1945, yang artinya berkaitan dengan kelembagaan BPK, baik yang berhubungan dengan kedudukan tugas, fungsi dan kewenangan serta hal-hal lainnya, kemudian akan diatur kembali dengan suatu UU yang bersifat khusus untuk itu, misalnya sekarang telah ada UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. 5. Mahkamah Agung (MA) Terkait dengan Mahkamah Agung telah ditegaskan kembali, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam melakukan tugasnya dan kewenangannya, kemudian hal tersebut ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 (lihat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
344
juga ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Di samping adanya Mahkamah Agung, dalam kenyataannya terdapat pula Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahkan pada dasarnya kedua lembaga tersebut kedudukan sejajar dalam UUD 1945 (lihat juga ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009). UUD 1945 setelah mengalami amandemen, ternyata telah merubah ketentuan tentang kekuasaan kehakiman khususnya berkaitan dengan Mahkamah Agung, untuk itu dapat dilihat kembali hasil daripada perubahan tersebut, yaitu sebagai berikut. BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang (kursif penulis). Sebelum adanya perubahan terhadap UUD 1945, berkaitan dengan pengaturan Mahkamah Agung di Bab X tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya dalam ketentuan Pasal 24 dan 25 UUD 1945, ternyata hanya terdiri dari dua pasal disertai pula dengan dua ayat. Pasal beserta ayat sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas dapat dilihat kembali di bawah ini. Pasal 24 1. Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. 2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undangundang. Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang (kursif penulis).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
345
Hasil amandemen UUD 1945, telah berhasil merombak kedudukan dan fungsi daripada kekuasaan kehakiman, yaitu dengan cara lebih mempertegas kembali tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dapatlah diketahui bahwa UUD 1945 menjamin pelaksanaan fungsi dan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Ketentuan ini kemudian akan lebih menegaskan kedudukan Mahkamah Agung, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang tidak dapat diintervensi oleh kekuatan apapun dalam bentuk apapun, untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat dari UUD 1945, guna menegakan hukum dan keadilan. Ketentuan yang sama, yaitu berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dapat pula kita temui kembali dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (kursif penulis). Adanya pengaturan yang tegas seperti tersebut di atas, tentunya akan berbeda sekali dengan sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, yang sebelumnya tidak secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka, atau dengan kata lain bahwa tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Namun, jika kemudian kita lihat kembali ke dalam UUD 1945 sebelum diamandemen, terutama berkaitan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, ternyata hanya dapat kita temui dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, yang pada dasarnya menyatakan bahwa. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim (kursif penulis). Agar hakim dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tenang, tentram serta agar peradilan terlaksana secara fair, menurut hukum, tidak memihak, tidak semena-mena dan adil, maka perlu adanya jaminan (Mertokusumo,2011;135). Dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945 tersebut, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah sebuah kekuasaan yang merdeka atau independen, terutama dalam membuat sebuah keputusan tanpa adanya pengaruh darimanapun dalam bentuk apapun, baik oleh legislatif maupun eksekutif, masyarakat dan pers serta lain-lain di luar badan peradilan dalam menjalankan tugas
I Gusti Ngurah Santika, SPd
346
konstitusionalnya. Terkait dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia. Tujuan daripada kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah untuk dapat menjamin tegaknya hukum dan keadilan, bahkan dapat dikatakan sebagai prasyarat utama agar mampu mewujudkan negara hukum yang benar-benar berkedaulatan rakyat berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Menurut Mahmud MD (2010;87) bahwa kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan kekuatan di luarnya merupakan masalah esensial dalam penegakan hukum. Jadi, prasyarat utama untuk tegaknya hukum adalah bebasnya badan peradilan dari campur tangan di luar kekuasaan kehakiman. Karena jika saja badan peradilan dicampuri urusannya dalam menegakan hukum dan keadilan, yang terjadi hanyalah jatuhnya keadilan ke dalam kesewenang-wenangan hakim, yang kemudian semuanya tersebut tercermin dari putusannya, yang tentunya tidak dapat memenuhi rasa keadilan. Untuk itulah Najih (2008;8) selanjutnya menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, jelas dinyatakan bahwa untuk tegaknya hukum dan keadilan diperlukan adalah adanya jaminan terhadap peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak kepada siapapun, kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Tidak memihaknya kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan dapat dilihat kembali dari putusan-putusan yang kemudian dihasilkan. Tentunya putusan hakim tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, serta memperhatikan pula rasa keadilan yang betul-betul hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan jaminan dalam menegakan hukum demi tercapainya keadilan. Karena kekuasaan kehakiman yang merdeka, merupakan pencerminan utama daripada suatu negara untuk kemudian dianggap sebagai negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai derajat tinggi, terutama dalam menegakan hukum untuk akhirnya mencapai keadilan. Bahkan, Utama (2007;34) dengan tegas menyatakan bahwa badan peradilan di negara hukum, merupakan sub sistem hukum yang paling kentara sekaligus, menjadi wujud nyata bekerjanya hukum. Pernyataan di atas
I Gusti Ngurah Santika, SPd
347
tidaklah berlebihan, dikarenakan bahwa keputusan badan peradilan merupakan kata akhir bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, pada akhirnya semua keputusan penentu nasib manusia berada pada tangan hakim, sebagai organ yudikatif yang bertugas untuk memberi keputusan hukum atas proses hukum selama ini yang dijalani oleh para pencari keadilan. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa ujung tombak daripada negara hukum adalah terletak pada kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Walaupun mungkin aparat penegak hukum yang lainnya dalam menjalankan kekuasaannya, ternyata tidak mampu menegakan hukum sebagaimana yang sebelumnya dikehendaki oleh masyarakat. Namun, dengan adanya kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugasnya, tentunya akan lebih mampu untuk mengurangi lunturnya keadilan, bahkan dapat mendongkrak berdirinya negara hukum yang demokratis. Lembaga peradilan yang merdeka merupakan suatu upaya pencegahan terhadap kekuasaan sewenang-wenang daripada negara, yang sebelumnya memang telah terbukti dalam lintasan sejarah. Bahkan, lebih tegas lagi Huijbers (2011;87) menyatakan bahwa prinsip kedaulatan kekuasaan yudikatif sangat mendorong perkembangan negara hukum. Untuk itu, ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman merupakan pedoman utama di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, sehingga dapat tercapainya negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Negara hukum yang dimaksud di sini adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa, yang tentram aman, sejahtera, dan tertib, dalam mana kedudukan hukum warga negara dalam masyarakat dijamin, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan masyarakat (Soemitro,1998;1-2). Seomitro dalam pernyataannya telah memberikan pedoman untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu selalu berpedoman dan bercermin pada nilai-nilai luhur yang menjadi kesepakatan bangsa, yaitu Pancasila. Tentunya keputusan yang diambil oleh hakim dalam menjalankan tugasnya tidak akan terlepas dari kelima nilai tersebut di atas, sebagai dasar untuk mengambil keputusan, dengan tujuan untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Jika dituruti kemudian kelima sila tersebut sebagai acuan utama dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan, niscaya terkait dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman akan selalu tercermin kemudian dalam setiap keputusannya, yang mana tentunya selalu bersifat objektif, serta mampu mencerminkan independensinya dalam menegakan hukum dan keadilan, untuk tercapainya negara hukum yang demokratis. Lebih lanjut terkait dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka Azhary (tt;97) memberikan pengertian kemerdekaan yudisial sebagai kemerdekaan dari segala macam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
348
bentuk pengaruh dan campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Tentunya, tidak hanya dari eksekutif maupun legislatif yang kemudian dapat menjadi sumber dari ketidakmerdekaan hakim di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Namun, mungkin dapat saja disebabkan oleh kekuasaan lainnya, seperti masyarakat, pers, serta kekuatan ekonomi. Namun, tidak kurang pentingnya untuk disebutkan adalah dengan cara mengurangi penyebab seperti tersebut di atas, yaitu berupa keberanian hakim sebagai modal dalam menegakan hukum dan keadilan, merupakan salah satu prasyarat untuk merdekanya kekuasaan kehakiman dari pengaruh yang datang dari luar. Mertokusumo (2006;46) memandang bahwa asas kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa. Yang dimaksudkan dengan kebebasan peradilan atau hakim ialah bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil. Pendapat dari Mertokusmo tersebut di atas, merupakan suatu pendapat yang sifatnya paling luas, dari berbagai pendapat sebelum-sebelumnya, karena dengan menyatakan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil. Dengan demikian, jika saja intervensi kemudian datang dari dalam kekuasaan yudisial, maka hal tersebut tentunya bisa saja dibenarkan. Dalam pada itu, dapatlah dicontohkan kemudian, terutama terkait dengan bidang tingkatan peradilan dalam mengambil keputusan, misalnya dapat saja putusan dari pengadilan negeri yang dikarenakan adanya banding, kemudian dinyatakan batal oleh pengadilan tinggi yang merupakan pengadilan lebih tinggi kedudukannya, kemudian ternyata keputusan dari pengadilan tinggi tersebut, berlanjut kembali dengan adanya permintaan kasasi, yang selanjutnya dapat saja kemudian dibatalkannya keputusan dari pengadilan tinggi tersebut oleh Mahkamah Agung, tiada lain dikarenakan MA merupakan puncak daripada keempat peradilan yang ada di bawahnya. Ketentuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari campur tangan di luar kekuasaan kehakiman, dapat pula kita temukan kembali dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (kursif penulis). Dengan demikian, campur tangan oleh badan peradilan yang kedudukannya lebih tinggi, terhadap badan peradilan yang lebih kedudukannya rendah dengan jalan membatalkan keputusannya tersebut, dapatlah dibenarkan kemudian. Ini merupakan suatu upaya dalam bentuk mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan. Kemudian ada pula tujuan lainnya, yaitu merupakan suatu upaya untuk mencapai unifikasi hukum serta
I Gusti Ngurah Santika, SPd
349
penyamaan persepsi dalam hukum. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan adanya mekanisme seperti itu, tidaklah kemudian dikatakan telah mengurangi, menggerogoti, bahkan mempengaruhi kebebasan hakim dalam menentukan pertimbangan untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal ini, berarti tidak dibenarkan untuk mempengaruhi hakim baik dengan melalui tekanan, paksaan maupun karena kekuasaan yang dimilikinya sehingga hakim merasa tidak bebas dalam memberikan keputusan (Afandi,1981;65). Tidak lain tujuan utamanya adalah agar pengadilan benar-benar dapat menjadi benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan (Nasution,2007;6). Karena peradilanlah merupakan tempat yang terakhir bagi pencari keadilan, untuk meminta keputusan adil tanpa kemudian dipengaruhi oleh pihak lain. Karena adanya pengaruh dari pihak lain dalam peradilan, dapat saja kemudian menyebabkan hakim terpengaruh, untuk memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan, diharapkan ke depannya peradilan benar-benar mampu memenuhi semua harapan dari para pencari keadilan, bukannya sebaliknya, yaitu mempersulit, bahkan menghambat sert merintangi mereka untuk memperoleh keadilan. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (kursif penulis) (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Dalam pada itu, akan berbeda sekali dengan UU No 19 Tahun 1964, yang kemudian dalam ketentuan undang-undang tersebut, diatur tentang tidak adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari pengaruh eksekutif. Perlu untuk diketahui kembali, ketika itu adanya ketentuan tersebut merupakan suatu penyimpangan yang dapat dikatagorikan mendasar, antara lainnya dengan memberikan wewenang kepada Presiden, dalam beberapa hal untuk dapat turut campur tangan berkaitan dengan soal-soal pengadilan. Dengan demikian, adanya UU No. 19 Tahun 1964, menurut Lubis (1987;197) merupakan suatu penyimpangan dari prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus independent yaitu lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, consideren UU itu, menilai UU No 19 Tahun 1964 itu sebagai memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dan DPR tersebut, pada dasarnya adalah sangat bertentangan dengan jiwa konstitusi. Walaupun dalam kenyataan telah ditentukan dalam konstitusi, bahwa undang-undang tersebut dibuat oleh lembaga demokrasi, namun jika dalam kenyataannya bertentangan dengan prinsip hukum, terutama dengan kebebasan kehakiman adalah harusnya dibatalkan atau batal demi hukum. Sehingga, Supriyanto (2004;10) kemudian berpendapat bahwa the Independence of
I Gusti Ngurah Santika, SPd
350
Judiciary is core element of supremacy of law and democracy) yang sangat didambakan, dapat terwujud. Walaupun untuk dapat mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman sangatlah tidak mudah untuk mengukurnya, namun dapatlah kemudian dilihat daripada keputusan-keputusan yang diambilnya, tentunya disertai dengan pertimbanganpertimbangan hakim, yang kemudian dikeluarkannya untuk menjawab pertanyaan para pencari keadilan. Peran Lembaga Peradilan, yaitu untuk menjamin penerapan hukum dalam masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan mencapai sasaran (Perwita dan Yani,2011;114). Lebih lanjut bagi negara yang meletakan rakyat sebagai sumber daripada kedaulatan, maka berdasarkan pemikiran tersebut masyarakat kemudian dapatlah melakukan kontrol terhadap proses peradilan, apakah selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya hakim dapat mencerminkan kemerdekaannya, untuk menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itulah, kemudian dalam ketentuan dari Pasal 13 ayat (1) dan (1) UU No. 48 Tahun 2009, pada intinya mengamanatkan agar semua sidang pemeriksaan dalam proses peradilan dilaksanakan secara terbuka untuk umum, bahkan juga termasuk putusannya haruslah kemudian diucapkan di depan pengadilan yang terbuka untuk umum. Apabila hal tersebut tidak dituruti maka berakibat batalnya putusan yang diambil oleh hakim. Sidang tertutup memang dapat saja dibenarkan, apabila kemudian dalam undangundang menentukannya dengan tegas, namun tetap saja keputusan hakim tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Contoh dari sidang pengadilan tertutup seperti berkaitan dengan kesusilaan, perceraian, dll. Perlu ditegaskan kembali berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, seperti sebelum diamandemennya UUD 1945. Karena dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen, ternyata menentukan bahwa selain adanya Mahkamah Agung, dalam kenyataanya terdapat pula Mahkamah Konstitusi, yang berdiri di sampingnya serta memiliki peran sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, bahkan pada dasarnya memiliki kedudukan sama pula. Ketentuan yang sama dapat dijumpai kembali dalam ketentuan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, yang selanjutnya mengatur tentang pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dengan keempat badan peradilan yang berada di bawahnya, serta terdapat Mahkamah Konstitusi yang berdiri di sampingnya. Tentunya berkaitan kedudukan Mahkamah konstitusi terpisah dengan Mahkamah Agung, selain adanya perbedaan tugas dan wewenang lainnya, seperti apa yang memang telah ditentukan dalam UUD 1945. Dengan demikian, terdapat dua lembaga negara yang pada dasarnya merupakan pelaksana daripada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun, bedanya adalah berupa tugas dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
351
kewenangan yang telah ditentukan di dalam UUD 1945, termasuk pula dalam hal ini berkaitan dengan struktur dari keempat peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, tidaklah dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Perlulah kemudian untuk diketahui selanjutnya terkait dalam menjalankan kekuasaannya, yaitu Mahkamah Agung, dalam kenyataannya terdapat lembaga negara lainnya yang bertugas pula untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, yang secara struktural ternyata tidak berada di bawahnya atau dengan kata lain bahwa pada intinya kedua lembaga negara tersebut tidaklah memiliki hubungan, karena memang keduanya lembaga negara tersebut terpisah satu sama lain menurut UUD 1945. Sehingga ,jika kita simak kembali ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 terlihatlah bahwa dari rumusan ini kemudian dapat disimpulkan bilamana kekuasaan kehakiman ternyata terbagi dalam 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court) yang berpuncak pada MA dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK (Wasito dkk,2010;593). Dengan kata lain, bahwa reformasi di bidang hukum (amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (Triwulan dan Widodo,2011;83). Karena untuk sekarang telah ada lembaga negara lainnya, yang juga ikut terlibat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (constitutional court) Berkaitan dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang ditentukan merdeka, dengan empat badan peradilan yang berada di bawahnya. Maka setelah adanya reformasi terhadap UUD 1945, berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, juga diperkenalkan sebuah lembaga negara baru yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Menurut Asshiddiqie (2006;41) bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah lembaga independen yang sama sekali terpisah dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi peradilan (rechtsprekende functie) dan fungsi pengaturan (regelende functie), kedua mahkamah ini bersifat independen dari segala bentuk intervensi. Fatmawati (2005;17) kemudian menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga negara yang dijamin kemerdekaannya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan yang berkaitan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, tentunya sangat penting bagi Mahkamah Agung di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanat UUD 1945, agar kemudian tercipta negara hukum yang bersifat demokratis. Karenanya, Manan dan Magnar (1997;40) menyatakan bahwa
I Gusti Ngurah Santika, SPd
352
baik menurut paham kedaulatan (demokrasi) maupun paham negara berdasarkan atas hukum (der rechtsstaat atau the rule of law, kekuasaan kehakiman yang bebas, merupakan unsur mutlak untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum. Tanpa adanya kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman, yang selanjutnya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, maka kedaulatan rakyat akan mudah tergelincir, sehingga menjadi anarki. Dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim diwajibkan untuk tetap mempertahankan kemandirian sistem peradilan. Ini artinya bahwa asas imparsial dan bebas merdeka itu tidak boleh digunakan sebagai perisai dalam melindungi anasir-anasir negatif yang mungkin saja bermain ketika peradilan memutus perkara (Asshiddiqie dan Syahrizal,2012;91). Ini membuktikan bahwa kekuasaan kehakiman ternyata begitu rentan terhadap intervensi dari kekuasaan-kekuasaan lain, yang pada akhirnya menginginkan agar kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, untuk menghadapi tekanantekanan penguasa terhadap lembaga peradilan merupakan suatu keniscayaan, yang harus selalu dilakukan oleh lembaga peradilan, terutama oleh hakim agar dikemudian hari tetap independen dalam memutus kasus. Kekuasaan lainnya akan selalu saja mencoba, untuk melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Kecuali itu, dikarenakan bahwa peradilan merupakan suatu kekuasaan (dalam arti functie), yang berdiri sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya (Basah,1985;28). Kekuasaan dimaksud dalam hal ini adalah kekuasaan yang datang dari eksekutif, legislatif, serta partai politik, pers dan lain-lainnya, yang sewaktu-waktu dapat saja kemudian mengintervensi daripada kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya yang berat, sebagai suatu lembaga negara bertujuan untuk menegakan hukum dan keadilan. Maka ke depannya tentu diperlukan orang-orang yang benar-benar bijaksana, untuk kemudian dapat menjadi hakim agung dalam menjalankan tugasnya yang mulia. Sebutan atau kata Agung mencerminkan betapa tinggi nilai lembaga, sekaligus terkandung pengertian betapa besar kewajiban yang diletakan pada lembaga tersebut untuk menegakan keadilan (Ranadireksa,2009;223). Oleh karenanya, tumpuan utama yang hendak diletakan oleh rakyat melalui UUD 1945, kepada Mahkamah Agung haruslah kemudian dilaksanakan dengan konsekuen. Tidak lain disebabkan tanpa itu, hukum yang sebenarnya menjadi tumpuan utama dalam mencari keadilan, tidak mungkin mampu memberikan suatu perlindungan yang nyata bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sebagamana amanat dari UUD 1945. Untuk menegakan keadilan, maka untuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
353
sekarang diperlukan hakim yang benar-benar memiliki kemampuan dan integritas, tentunya juga dapat memahami amanat yang dibebankan kepadanya secara konstitusional. Bahkan, menurut Setiyono (2008;33) bahwa hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat hukum. Untuk itu, perlukan hakim yang jujur dan berani dalam menegakan hukum seperti apa yang memang sebenarnya diamanatkan oleh lembaganya yang tentunya merdeka, sehingga benar-benar mampu memberikan keputusan yang sifanya objektif, di samping dapat memenuhi harapan para pencari keadilan. Sekalipun putusan hakim yang diambil belum tentu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, namun bisa saja karena hakim tersebut memiliki perasaan keadilan. Sehingga dengan keberaniannya dapat memberi dasar-dasar putusan yang dapat diterima, di samping juga dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara yuridis, sosial, serta moral, namun tetap dengan menjungjung tinggi Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dinyatakan, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (kursif penulis) (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Berkaitan dengan struktur organisasi Mahkamah Agung, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan puncak dari keempat badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Bahkan, Mahkamah Agung merupakan badan peradilan yang tertinggi daripada peradilan yang berada di bawahnya (lihat Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009). Asshiddiqie (2003;34) menyatakan ditinjau dari segi hubungan hakim dalam kelembagaan tersebut bahwa hubungan antar satu hakim dengan hakim yang lain besifat horizontal, tidak ada hubungan vertical atasan dan bawahan. Lebih lanjut menurutnya semua pendapatnya tersebut timbul dari doktrin kebebasan atau kemerdekaan hakim, yaitu setiap individu hakim dalam menjalankan tugas utamanya sebagai hakim yang bersifat bebas dan merdeka tidak bertanggung jawab kepada atasannya. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Kelsen (2011;390) bahwa para hakim biasanya bebas yakni, mereka hanya tunduk kepada hukum dan tidak tunduk kepada perintah atau intruksi dari organ yudikatif atau administratif yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan, ke atas hakim bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ke bawah bertanggungjawab secara hukum. Semua hal tersebut, adalah sesuai
I Gusti Ngurah Santika, SPd
354
dengan adanya doktrin kebebasan kekuasaan peradilan. Bahkan, berkaitan dengan kebebasan hakim Soepomo (2005;67) berpendapat bahwa di mana undang-undang memberi peraturan, hakim adalah bebas di dalam menentukan keputusannya. Terkait dengan peradilan yang secara struktural berada di bawah Mahkamah Agung, maka Kusnardi dan Sarigih (1986;84) kemudian berpendapat bahwa hubungan Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkaraperkara tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara pidana maupun perkara perdata. Karena dalam peradilan militer yang terkait di sana adalah berkenaan dengan kepentingan militer, sedangkan peradilan agama adalah peradilan yang khusus yang berkaitan dengan agama Islam, sedangkan peradilan tata usaha negara merupakan berkaitan dengan tindakan penyelenggara tata usaha negara yang merugikan rakyat, maka dapat dimintakan putusan peradilan tata usaha negara tentang tindakan pemerintah tersebut. Untuk selanjutnya, dalam kenyataannya masih diakuinya adanya badan-badan lainnnya, selain sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (3) UUD 1945). Dalam Penjelasan Pasal 38 UU No. 48 Tahun 2009, dalam kenyataannya ketentuan tersebut memberikan penafsiran terhadap pengertian badan-badan lainnya yang bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, bahwa Yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada intinya lembaga-lembaga sebagaimana dimaksudkan di atas, tentunya memiliki keterkaitan fungsi secara nyata atau bersentuhan dengan kekuasaan kehakiman. Adanya ketentuan ini merupakan jalan keluar bagi tidak dimasukannya kejaksaan, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada saat berlangsungnya amandemen UUD 1945. Pencantuman ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 di atas juga merupakan suatu antisipasi terhadap perkembangan yang mungkin saja terjadi pada masa yang akan datang, misalnya kalau ada perkembangan terhadap badan-badan peradilan lain yang tidak
I Gusti Ngurah Santika, SPd
355
termasuk dalam kategori keempat lingkungan peradilan yang sudah ada, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentu kemudian kedudukan badan-badan peradilan selain yang sudah ditentukan dalam UUD 1945, dapatlah dikatakan tidak berbeda dengan badan-badan lainnya yang juga melaksanakan kekuasaan kehakiman, walaupun ditentukan dalam undang-undangan. Hal ini dikarenakan, baik badan-badan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 maupun kejaksaan misalnya, dalam kenyataaannya memiliki kedudukan sama penting dalam konsitusi atau sama-sama penting secara konstitusional. Terkait dengan adanya ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, MPR (2011;147-148) menyatakan bahwa. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) menjadi dasar hukum keberadaan berbagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Hal-hal mengenai badan lain itu diatur dalam undang-undang. Pengaturan dalam undang-undang mengenai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman membuka partisipasi rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR untuk memperjuangkan agar aspirasinya dan kepentingannya diakomodasi dalam pembentukan undang-undang tersebut. Adanya ketentuan pengaturan dalam undangundang tersebut merupakan salah satu wujud saling mengawasi dan mengimbangi antara kekuasaan yudikatif MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK dengan kekuasaan legislatif DPR dan dengan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Selain itu, ketentuan itu dimaksudkan untuk mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated judiciary system) di Indonesia. Pencantuman Pasal 24 ayat (3) di atas juga untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, kalau ada perkembangan badan-badan peradilan lain yang tidak termasuk dalam katagori keempat lingkungan peradilan sudah diatur dalam undangundang. Selanjutnya pengaturan berkaitan dengan kewenangan, syarat-syarat untuk menjadi hakim agung dan juga proses pengangkatan hakim agung, di samping berkaitan dengan tata cara pemilihan Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung, telah ditentukan dengan tegas dalam ketentuan Pasal 24A UUD 1945, yang menyatakan bahwa. (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
356
(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung yang telah ditentukan dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1), maka pada dasarnya pasal ini menegaskan bahwa dalam UUD 1945, Mahkamah Agung diberikan dua kewenangan secara konstitusional yaitu (1) mengadili pada tingkat kasasi, dan (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan, kewenangan lainnya, merupakan kewenangan yang didelegasikan oleh pembentuk undangundang. Dengan kata lain, bahwa kewenangan tersebut merupakan bersifat tambahan yang tidak diberikan oleh UUD 1945, namun oleh UU (Asshiddiqie,2006). Pengaturan yang sama kemudian juga dapat dilihat kembali dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan kewenangan Mahkamah Agung, yaitu. a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung yang mengadili pada tingkat kasasi, maka menurut Subekti (1983;105) bahwa perkataan kasasi berasal dari perkataan Perancis casser yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga kalau suatu permohonan kasasi terhadap suatu putusan Pengadilan bawahan diterima oleh Mahkamah Agung, maka itu berarti bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan penerapkan hukum. Sedangkan, untuk kamus istilah hukum Fockema Andreae dalam Marpaung (2004;3) menyatakan bahwa cassatie, kasasi, pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan Hakim rendahan oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan. Menurut penulis kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pengadilan di bawahnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
357
(banding), merupakan salah satu bentuk pengawasan Mahkamah Agung dari dalam, terutama terkait dengan penerapan hukumnya. Menurut Mertokusumo (2011;131) bahwa kasasi adalah peradilan, sedang peradilan berarti pelaksanaan hukum, maka pada hakikatnya tujuan kasasi bukanlah mencapai kesatuan hukum, melainkan kesatuan dalam pelaksanaan hukum atau kesatuan dalam peradilan. Bahkan, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap pun masih dapat dimintakan peninjauan kembali, tentunya jika karena keadaan tertentu yang kemudian dapat diterima oleh undang-undang (lihat Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009). Dapatlah kemudian dikatakan, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan peradilan yang ada di bawahnya merupakan tugas utama daripada Mahkamah Agung dalam bidang pengawasannya. Pendapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 48 Tahun 2009 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (kursif penulis). Bahkan, pengawasan MA sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tentunya juga meliputi pengawasan tertinggi terhadap pelaksana tugas administrasi dan keuangan. Selain itu, ternyata pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim dilakukan juga oleh MA. Namun, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pula pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai tugas utama, yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Namun, pada dasarnya ditentukan bahwa kedua pengawasan, baik yang dilakukan oleh internal MA maupun KY secara eksternal, tentunya tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Katamenguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah merupakan hak MA untuk melaksanakan tugasnya berkaitan penyesuaian bidang peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, agar nantinya tidak ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam kenyataannya bertentangan dengan kedudukan undang-undang yang berada di atasnya. Hal ini berarti jika suatu saat ada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, yang benar-benar bertentangan dengan undang-undang di atasnya, maka terhadap peraturan tersebut kemudian dapatlah diuji dan dapat pula dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan untuk pengujian peraturan perundang-undang yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, dapat diuji dengan dua cara yaitu secara formil dan materiil. Terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan secara
I Gusti Ngurah Santika, SPd
358
materiil, maka Abdullah (2006;10) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hak uji Materiil adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Lebih jelas lagi, bahwa jika ternyata ada suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, yang kemudian dilihat dari segi isinya ternyata bertentangan dengan isi undang-undang, maka untuk itu selanjutnya dapat dimintakan pembatalan kepada Mahkamah Agung. Dengan kata lain, yang diuji merupakan keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum (Soemardi,1986;15). Adanya pengaturan hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari dianutnya prinsip hierarkis peraturan perundang-undangan, yang mana tentunya menyatakan bahwa suatu peraturan yang kedudukannya lebih rendah, isinya tidak boleh bertentangan dengan isi dari peraturan yang kedudukannya lebih tinggi tingkatannya (lex superior derogate legi inferiori). Dalam pada itu, tentunya akan berbeda dengan pengujian secara formal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, di mana jika ada suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang dalam kenyataan dibentuk tidak sesuai dengan prosedur, seperti apa yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang, maka secara keseluruhan daripada peraturan perundang-undangan, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Dari paparan tersebut, dapatlah kemudian ditarik suatu kesimpulan, bahwa jika pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang yang dilakukan oleh MA secara materiil, maka dapat dinyatakan batal adalah salah pasal atau bagian tertentu dari peraturan tersebut yang sebelumnya diminta untuk diujikan. Sedangkan, jika dalam kenyataannya pengujian peraturan perundang-undangan, yang berkedudukan di bawah undang-undang terhadap undang-undang-undang, ternyata dilakukan secara formil, maka akibatnya putusan dari pembatalan tersebut oleh MA, adalah secara keseluruhan peraturan perundang-undang yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, adalah batal dan tidak berlaku. Pengujian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dapat dilakukan melalui tingkat kasasi maupun secara langsung, yaitu dapat kemudian diajukan ke Mahkamah Agung. Kemudian permohonan tersebut cukup dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, baik oleh pemohon maupun kuasanya. Pendapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
359
langsung pada Mahkamah Agung (kursif penulis). Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundangundangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat. Berkaitan dengan kewenangan MA yang hanya menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, maka Mahkamah Agung tidaklah memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pendapat tersebut adalah sesuai dengan apa yang kemudian dinyatakan oleh Kartasapoetra (1987;69) bahwa pada dasarnya Mahkamah Agung tidak mempunyai hak menguji, baik formal maupun material terhadap undang-undang. Mengenai upaya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dapat dikatakan merupakan upaya pengujian legalitas (legal review). Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini jelas berbeda dari pengujian konstitusional (constitutional review) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, obyek yang diuji hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undangundang (judicial review of regulation). Hal ini dikarenakan, pengujian arah konstitusionalitas undang-undang (judicial riview of law) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, yang dijadikan batu penguji oleh Mahkamah Agung adalah undangundang, bukan UUD. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian norma hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengujian legalitas peraturan (judicial review on the legality of regulation), sedangkan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review on the constitutionality of law). Yang terakhir ini biasa di sebut dengan istilah pengujian konstitusional atas undang-undang (constitutional of law) (Asshiddiqie,2006;158). Dalam ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 ditentukan pula syarat untuk dicalonkan menjadi hakim agung. Kemudian dinyatakan bahwa untuk menjadi hakim agung haruslah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional yang tentunya berkaitan dengan keahliannya dalam bidang hukum dan sudah memiliki pengalaman sesuai dengan keahliannya di bidang hukum tersebut (lihat ketentuan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Calon hakim agung kemudian ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, yang sebelumnya diajukan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
360
oleh KY (Pasal 24A ayat (3) UUD 1945). Jumlah calon hakim agung yang diajukan oleh KY ke DPR adalah tiga kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan untuk menjadi hakim agung (lihat ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009). Kemudian, selanjutnya ditentukan bahwa untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diserahkan kembali kewenangannya kepada anggota hakim agung sendiri untuk kemudian memilihnya (Pasal 24A ayat (4) UUD 1945) jo. (Pasal 8 ayat (7) UU No. 3 Tahun 2009). Terkait dengan susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan yang kedudukannya berada di bawahnya diatur kembali dengan bentuk undangundang (Pasal 24A ayat (5) UUD 1945). Undang-undang yang di maksud adalah UU No.14 tahun 1985 jo. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Selain adanya tugas seperti apa yang telah disebutkan di atas, ternyata MA memiliki tugas dan kewenangan lainnya, misalnya untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden berkaitan dengan pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 UUD 1945). Kemudian dapatlah diketahui bahwa berkaitan dengan pertimbangan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden, terkait dengan pemberian grasi dan rehabilitasi tersebut, tentunya tidaklah mengikat secara hukum. Namun, dapatlah dikatakan mengikatnya pertimbangan Mahkamah Agung, berkaitan dengan pemberian grasi adalah terletak pada bidang moral. Selanjutnya juga ditentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengajukan 3 orang guna menjadi hakim konstitusi (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945). Berkaitan dengan semua tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Ketentuan ini merupakan hubungan MA dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaran Indonesia, yang merupakan wujud daripada saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). 6. Komisi Yudisial (KY) Latar belakang pembentukan pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian penting dari komitmen bangsa untuk dilakukannya reformasi multi dimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum, serta, keprihatinan yang mendalam atas praktek peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Agenda besar reformasi yang bergulir di tahun 1999, bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat adil dan sejahtera (Chotidjah,2010;168). Bobroknya kekuasaan kehakiman telah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
361
menyebabkan tidak berjalannya sistem hukum, yang seharusnya mampu menegakan kepastian hukum untuk kemudian mencapai keadilan. Bahkan, rendahnya kredibilitas daripada penegak hukum merupakan penyebab utama tidak tercapainya keadilan yang diharapkan. Rendahnya kredibilitas penegak hukum, terutama hakim telah membawa dampak yang cukup luas terhadap kepercayaan daripada para pencari keadilan terhadap dunia peradilan di tanah air. Rendahnya kredibilitas para penegak hukum, khususnya hakim tercermin dengan banyaknya terjadi berbagai tindak-tanduk prilaku hakim, baik yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum, bahkan jika dilihat dari sudut etika adalah tidak sesuai dengan jabatannya sebagai seorang hakim. Tidak adanya sebuah lembaga yang benar-benar mampu, untuk menegakan etika serta prilaku hakim yang pada dasarnya bersifat bertentangan, seperti sebagaimana dimaksud di atas. Dalam kenyataannya, semakin menambah daftar hakim yang berperilaku menyimpang, terutama dengan kewajiban utamanya sebagai seorang hakim. Sebenarnya jika kita dilihat kembali dengan saksama, ternyata tindakan hakim yang pada dasarnya bertentangan tersebut, dapat dilihat tidak hanya dari sudut hukum maupun etika sebagai seorang hakim. Telah menjadi penyebab utama para penegak hukum ini leluasa untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya menyimpang dari norma hukum maupun etika, yang tentunya bertentangan pula dengan kewajibannya sebagai seorang hakim. Dengan merosotnya etika hakim dalam berperilaku dimasyarakat, telah membawa implikasi yang dapat dikatakan luas terhadap penegakan hukum, terutama berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang telah ditentukan dalam UUD 1945, seharusnya merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan, bukan kemerdekaan untuk tujuan yang lainnya. Bahkan, terlihat dengan bobroknya moral hakim, yang kemudian tercermin dalam etikanya dimasyarakat, khususnya dalam menjalankan hubungan dinasnya, selalu saja menjadi topik utama setelah reformasi. Karena pada dasarnya reformasi itu sendiri sebenarnya, menuntut suatu peradilan yang sifatnya modern dan terpercaya, sehingga ke depannya mampu menegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Namun, dalam kenyataannya, reformasi ternyata belum mampu membawa dampak positif secara signifikan terhadap paradigma aparat penegak hukum, terutama hakim dalam berperilaku agar sesuai dengan kewajibannya. Apalagi kemudian diharapkan untuk mampu menegakan hukum dan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan (justiabelen), hal tersebut masih jauh dari pandangan hakim. Jika kita sejenak kembali ketika sebelum reformasi berjalan, tampak kemudian merosotnya kewibawaan peradilan, yang salah satu penyebabnya dikarenakan tidak berjalannya prinsip-prinsip peradilan, yaitu adanya kebebasan hakim dalam mengambil
I Gusti Ngurah Santika, SPd
362
suatu keputusan, dalam kenyataannya sangat berdampak terhadap kualitas putusan hakim, untuk memutuskan perkara demi tegaknya hukum dan keadilan. Bahkan, dalam kenyataan tidak jarang jika kekuasaan kehakiman, khususnya para penegak hukumnya (hakim) yang sedang menghadapi perkara, apalagi jika kemudian dalam perkara tersebut berhadapan secara langsung dengan pemerintah, seperti pada masa Orde Baru, maka akan terasa bahwa hakim tersebut terlihat tertekan untuk mengambil suatu keputusan yang tidak memihak. Dapatlah dikatakan bahwa yang menjadi penyebab tersebut, tidak lain dikarenakan pada waktu itu terkait dengan keorganisasiannya berada satu atap dengan Kementerian Kehakiman, yang dalam kenyataannya merupakan bagian daripada pemerintah. Dilain pihak, ada juga hakim-hakim tertentu yang dalam mengambil keputusan, walaupun pada dasar adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi ternyata dengan dalih bahwa hakim itu adalah bebas untuk mengambil keputusan, kemudian memanipulasi asas kemerdekaan hakim tersebut sebagai celah untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika hakim dalam berperilaku. Tentunya akan terlihat dengan jelas bahwa motivasi hakim dalam mengambil keputusan sebenarnya, sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya, yaitu menegakan hukum dan keadilan, yang sebenarnya diberikan oleh asas kemerdekaan kehakiman. Padahal kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan pijakan dasar bagi hakim, di samping dapat motivasinya dalam mengambil keputusan untuk mampu menegakan hukum dan mewujudkan keadilan, walaupun nantinya berhadapan dengan kekuasaan apapun di luar kekuasaan kehakiman. Kiranya sudah jelas bahwa bebasnya peradilan dari campur tangan kekuasaan extra-judisil akan membawa akibat pada meningkatnya wibawa atau supremasi hukum, salah satu faktor dari suatu negara hukum (Mertokusumo,2011;128). Kekuasaan kehakiman yang independen merupakan suatu keniscayaan bagi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan, namun dapat saja dengan dalih indepedensi kekuasaan yudikatif, kemudian hakim ternyata mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya terutama untuk mewujudkan tegaknya hukum dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, Maksudi (2012;141) menyatakan bahwa independensi kekuasaan yudikatif ini berusaha diimbangi dengan membentuk Komisi Yudisial. Jadi, Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman, sehingga tidak disalahgunakan baik oleh hakim yang berada di dalam kekuasaan peradilan tersebut, maupun kekuasaan yang kemudian berada di luar kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, selain pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai badan pengawas tertinggi internal prilaku hakim, maka telah dibentuk Komisi Yudisal yang merupakan pengawas eksternal terhadap prilaku hakim berdasarkan Kode
I Gusti Ngurah Santika, SPd
363
Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim. Suatu penegak hukum yang kemudian tanpa mendapatkan suatu pengawasan, terutama dari penegak Kode Etik, maka tentunya akan cenderung dapat menjadikan penegak hukum tersebut melakukan tindakan yang tentu saja menyimpang bahkan menjadi sewenang-wenang. Dan tentunya dapat saja kemudian, terjadi perbuatan yang dipandang tidak sesuai dengan apa, yang seharusnya dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut, terutama untuk menegakan hukum dan keadilan, yang tercermin dalam tindakannya sehari-hari benar-benar bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, maka dipandang perlu untuk dibentuk suatu lembaga negara, yang dapat diharapkan untuk mengawasi suatu penegak hukum, yang pada dasarnya penegak hukum tersebut adalah bebas dan merdeka untuk melakukan tugasnya, seperti apa yang telah diembankan oleh UUD 1945. Tentunya merupakan suatu tugas yang tidak mudah untuk dilakukan, sehingga harus benar-benar memiliki motivasi, dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan tugasnya, dalam bentuk pengawasan terhadap perilaku hakim, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Tentu untuk ke depannya diharapkan pengawasan yang dilaksanakan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial, tidaklah kemudian mengurangi daripada kebebasan hakim dalam memutus perkara. Dengan berdasarkan, pada penjelasan seperti apa yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka setelah adanya reformasi, perlulah dibentuk sebuah lembaga negara bernama Komisi Yudisial. Hal mana menurut Muqoddas dalam RifaI (tt;iv) bahwa tujuan visionernya adalah mereposisi dan merevitalisasi lembaga pengadilan dan proses peradilan dalam program-program aksi akseleratif menuju terciptanya pencapaian visi bangsa yaitu Indonesia sebagai negara berdasarkan prinsip The Rule of Law dan Kedaulatan Rakyat (The Souveregnity of the people). Hal tersebut diperlukan karena berkaitan dengan akuntabilitas aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif merupakan pilar yang menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan (ICCE UIN,2010;166). Cabang kekuasaan kehakiman sebagai pilar ketiga negara demokrasi yang berdasar atas hukum (principle of constitutional democracy) yang tercermin dalam kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, Komisi Yudisial berfungsi sebagai penjaga dan penegak kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Demokrasi perlu diimbangi dengan rule of law, dan berkembang efektifnya rule of law dan bahkan rule of just law sangat tergantung kepada keterpercayaan aparatur penegak hukum, khususnya para hakim. Karena itu, kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam sistem demokrasi konstitusional (Asshiddiqie,2006).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
364
Berikut ini merupakan latar belakang pembentukan Komisi Yudisial di berbagai negara, menurut Huda dalam Talhah dan Malian (2011;75), yaitu sebagai berikut. 1. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja; 2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power), dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman (judicial power); 3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukan dengan persoalanpersoalan teknis non hukum; 4. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; 5. Pola rekruitmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrut adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawas (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independensampai batas tertentusehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan (Mahkamah Agung,2010;73). Inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang, untuk kemudian dibentuknya KY di Indonesia, yang bertugas untuk menegakan etika para hakim berdasarkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Hal mana kalau dilakukan oleh dewan kehormatan dari dalam struktur yang akan diperiksa, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah saling melindungi korps. Keberadaan Komisi Yudisial diharapkan dapat memberikan sumbangsihnya dalam mewujudkan hakim agung yang mempunyai integritas dan moral (Asshiddiqie,2009;301). Kemudian, untuk mencapai suatu keadilan dalam negara demokrasi, diperlukanlah suatu lembaga negara yang nantinya diharapkan mampu untuk mengawasi, agar nilai-nilai keadilan serta keluhuran, yang kemudian tercermin dalam sifat maupun prilaku hakim tetap terjaga, sehingga betul-betul mampu merefleksikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga pengawas yang ditentukan bersifat mandiri, Komisi Yudisial memiliki
I Gusti Ngurah Santika, SPd
365
peranan sangat penting, untuk membantu hakim guna menjaga etikanya dalam berperilaku, sehingga mampu untuk menegakan hukum dan keadilan. Etika sendiri merupakan suatu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang di lakukan manusia untuk dapat dikatakan baik atau buruk, dengan kata lain aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Pengawasan terhadap etika hakim mutlak diperlukan, agar nilai luhur tetap terpancar, sebagai wujud daripada penegak keadilan.Tanpa adanya pengawasan hakim dari suatu lembaga negara yang juga bersifat bebas dan mandiri, maka pengawasan tersebut niscaya tidak akan mampu untuk menjadikan hakim, secara khusus, serta lembaga yudikatif secara umum menjadi lebih baik, namun dapat saja kemudian membuat peradilan menjadi semakin bobrok. Bahkan, berkaitan dengan pentingnya fungsi pengawasan, maka Siagian (2001;259) menyatakan pendapatnya bahwa: Secara konseptual dan filosofis, pentingnya pengawasan berangkat dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan operasional merupakan mahkluk yang tidak sempurna dan secara inheren memiliki keterbatasan, baik dalam arti interpretasi makna suatu rencana, kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan. Artinya, dengan itikad yang paling baik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan pengerahan kemampuan mental dan fisik sekalipun, para penyelenggara kegiatan operasional mungkin saja berbuat khilaf dan bahkan mungkin kesalahan. Kenyataan menunjukan bahwa tidak semua anggota organisasi yang selalu menampilkan prilaku demikian. Sengaja atau tidak, prilaku negatif ada kalanya muncul dan berpengaruh pada kinerja seseorang yang faktor-faktor penyebabnya pun beraneka ragam. Menghadapi kemungkinan demikianlah pengawasan mutlak perlu dilakukan. Setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, terkait dengan kekuasaan kehakiman, telah dibentuk pula suatu lembaga negara baru yang bernama Komisi Yudisial. Tugas utama lembaga tersebut adalah untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan prilaku hakim. Dasar pemikiran yang lebih jelas, untuk dibentuknya sebuah Komisi Yudisial, merupakan salah satu respon terhadap tanggapan masyarakat, terkait dengan bobroknya dunia peradilan di tanah air selama ini, terutama hakim di dalam menegakan hukum dan keadilan yang menjadi sorotan utama terkait lemahnya peradilan. Berikut ini merupakan hasil amandemen 1945, terkait dengan dibentuknya Komisi Yudisial, yaitu. Pasal 24B
I Gusti Ngurah Santika, SPd
366
1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undangundang(kursif penulis). Sedangkan dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, telah ditentukan pula, berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial, yaitu. a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dengan demikian, terkait dengan pengusulan pengangkatan hakim agung, maka Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan penyeleksian, kemudian hasil dari seleksi tersebut, diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui dan kemudian selanjutnya akan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Hanya saja tampak dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011, yang pada garis besarnya menyatakan bahwa Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan. Padahal, jika kemudian kita lihat kembali dalam ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden (kursif penulis). Jika demikian, maka penulis cenderung berpendapat kata dipilih dengan persetujuan tentunya memiliki arti yang berbeda. Kata dipilih tentunya menyatakan jumlah, dalam hal ini tentunya lebih mengacu pada kuantitas (jumlah), sedangkan untuk kata persetujuan menurut penulis adalah suatu pernyataan berupa kehendak yang terlepas
I Gusti Ngurah Santika, SPd
367
daripada jumlah (kuantitas), melainkan lebih mengacu pada kualitas, yang berarti bisa menyetujui ataupun tidak menyetujui. Dengan demikian, kesimpulan yang kemudian penulis dapatkan terkait masalah ini, adalah jika kita berpedoman kepada ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, tentunya berkaitan dengan kata persetujuan tersebut, sudah seharusnya dimaknai, bahwa suatu pernyataan yang memberikan dua pilihan, yaitu antara setuju atau tidak setuju. Namun, dalam UU No. 3 Tahun 2009 maupun dalam UU No. 18 Tahun 2011 ternyata kata persetujuan kemudian dirubah menjadi dipilih. Tentunya hal tersebut memiliki konsekuensi makna yang berbeda pula, di mana menurut pemahaman penulis, misalnya terkait dengan adanya kata persetujuan, yang mana jika saja suatu saat terdapat kekosongan di MA terkait dengan hakim agung, yang hanya diperlukan 1 orang saja, maka kemudian usul yang seharusnya disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada DPR adalah hanyalah 1 orang saja, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari DPR, apakah akan disetujui atau tidak. Sedangkan, jika kita menggunakan kata dipilih, maka jika membutuhkan 1 orang hakim agung misalnya, dapatlah kemudian mengajukan calon hakim agung lebih daripada 1 calon yang dibutuhkan, kemudian selanjutnya KY mengajukannya (berupa usul) ke DPR untuk selanjutnya dipilih salah satu daripada calon hakim agung, untuk mengisi kekosongan di MA tersebut. Mengenai pengawasan KY terhadap hakim, yang dalam kenyataannya duduk di lembaga negara, padahal bersifat merdeka atau independen dari kekuasaan lainnya sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk melaksanakan kekuasaannya telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Ternyata walaupun telah ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, namun ternyata kemerdekaan tersebut, belum tentu dapat memberikan jaminan pasti untuk sampai pada tegaknya hukum dan keadilan. Yang menjadi berbahaya adalah dengan dalih kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan, oknum hakim tertentu yang tidak memiliki tanggungjawab dapat saja dengan bebas, melakukan tindakan yang benar-benar sifatnya bertentangan, terutama dengan prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, hakim-hakim perlu dijaga agar prilakunya tersebut tidak menyebabkan keluhuran, dan kehormatan, serta martabat hakim jatuh di depan mata para pencari keadilan. Ini membuktikan bahwa jabatan hakim agung, merupakan suatu jabatan yang sifatnya terhormat, untuk kemudian wajib agar nantinya dijaga sehingga tetap bermartabat. Martabat hakim untuk kesehariannya tercermin dalam segala bentuk prilakunya, bertujuan untuk menegakan hukum serta mencapai keadilan dan kebenaran, yang kemudian dapat pula menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Sedangkan Moekri (2007;54) memberikan arti terhadap kata
I Gusti Ngurah Santika, SPd
368
menjaga dan menegakan, bahwa kata menjaga diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Kata menegakan diwujudkan dalam bentuk pendisiplinan atau pemberian sanksi disiplin. Dengan konsep yang demikian, maka Saifullah (2007;110) kemudian berpendapat bahwa konsepsi ini setidaknya dapat memelihara dan mengawetkan moralitas dari kontaminasi eksternal. Jika campur tangan datang dari pihak luar terhadap dunia peradilan, dapat saja berpotensi menjatuhkan hukum dan keadilan, di samping dapat pula menyebabkan kurangnya kepecayaan masyarakat dalam mencari keadilan ke pengadilan. Untuk itu, diperlukan seperangkat aturan, baik yang berbentuk etika, bahkan suatu aturan hukum yang menimbulkan sanksi bersifat memaksa bila dilanggar kemudian. Sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, bahwa untuk sekarang ini telah diatur pengusulan penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, bila nantinya ada hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim, hal mana semua itu telah diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 22D ayat (3) UU No. 18 Tahun 2011. Dalam pada itu, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Penjatuhan sanksi oleh Mahkamah Agung akan dilakukan secara otomatis, tentunya jika tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan penjatuhan sanksi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Namun, dalam UU No. 22E ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 memberikan solusi, misalnya jika ada perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial berkaitan dengan penjatuhan sanksi. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Kata sepakat sebagamana dimaksud dalam ayat (2) dimaksud adalah berkenaan dengan terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Dalam Pasal 22D ayat (2) telah ditentukan jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan/ Pedoman Prilaku Hakim. Misalnya dalam bentuk sanksi ringan terdiri atas; (a) teguran lisan; (b) teguran tertulis; atau (c) pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi yang bersifat sedang terdiri atas; (a) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; (b) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; (c) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu ) tahun; atau (d) hakim nonpalu paling lama 6 (enam)
I Gusti Ngurah Santika, SPd
369
bulan. Untuk sanksi yang sifatnya beratnya terdiri atas; (a) pembebasan dari jabatan struktural; (b) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; (c) pemberhentian sementara; (d) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau (e) pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Terkait dengan penjatuhan sanksi, secara otomatis berjalan walaupun Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak mendapat kesepakatan bersama, hal tersebut dikarenakan sudah memenuhi syarat bahwa hakim yang bersangkutan telah terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim. Pemeriksaan dilakukan secara bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dapatlah dikecualikan bilamana kemudian sanksi yang hendak dijatuhkan adalah pemberhentian tetap dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Terkait dengan pengecualian pemeriksaan yang menyangkut pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim yang mengarah pada penjatuhan sanksi pemberhentian tetap dan pemberhentian tidak tetap, dikarenakan selain dari kedua sanksi itu pemeriksaan dilakukan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pernyataan tersebut dilontarkan dikarenakan bahwa dalam ketentuan Pasal 22F ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau Pedoman Etik sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada Komisi Yudisial. Tidak lain, disebabkan sanksi yang diancamkan kepada hakim karena melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim adalah tergolong sanksi yang sangat berat yakni, pemberhentian tetap dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Yang kemudian menjadi dasar pemikiran tersebut, yaitu tentunya akan lebih baik jika Komisi Yudisial sebagai lembaga eksternal yang kedudukannya berada di luar struktural kekuasaan kehakiman untuk diberikan kewenangan sebagai pemeriksa terhadap pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim. Adanya ketentuan tersebut setidaknya akan mampu menghindari rasa segan terhadap sesama hakim, yang tentunya sama-sama masih dalam satu institusi. Tetapi jika kemudian kita lihat kembali pengaturan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22F ayat (3) UU No. 18 Tahun 2011, ternyata Mahkamah Agung pun memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim, terkait menimbulkan sanksi yang digolongkan berat, seperti pemberhentian tetap dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil dari sini adalah pemeriksaan yang dilakukan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah terpisah. Tentunya adanya pernyataan tersebut tidak lain bertujuan untuk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih objektif, sehingga dapatlah kemudian mengurangi unsur-unsur yang sifatnya politis, dikarenakan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
370
adanya perbedaan pendapat di antara dua institusi tersebut, yang sama-sama berbeda dalam melakukan pemeriksaan. Namun, untuk memutuskan apakah dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ Pedoman Prilaku Hakim terbukti atau tidak sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Yudisial ternyata tidaklah berwenang untuk melakukannya, bahkan Mahkamah Agung pun tidak memiliki kewenangan dalam hal ini. Kewenangan untuk memutuskan daripada hasil pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang dilakukan secara terpisah, akan diuji kembali objektivitasnya dalam sebuah Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus, adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dalam ketentuan Pasal 22F ayat (3) UU No. 18 Tahun 2011, menyatakan bahwa : Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung (lihat Pasal 22F ayat (2) UU No.18 Tahun 2011). Dengan komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim yang demikian, tentunya Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang lebih menguntungkan, terutama jika dilihat dari sudut politis, apabila kemudian dibandingkan dengan kedudukan Mahkamah Agung. Dikarenakan suatu saat apabila terjadi permusyawaratan yang pada akhirnya berujung tidak tercapai kata mufakat, atau dengan kata lain terjadi perbedaan pendapat dalam memeriksa dalam memutuskan kasus tersebut, maka oleh Majelis Kehormatan Hakim selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk memutuskannya. Dikatakan KY memiliki keuntungan, tidak lain dikarenakan bahwa secara politis dalam Majelis Kehormatan Hakim yang di dalamnya terbentuk dari gabungan dua lembaga negara (KY dan MA) yang tentunya bersifat sementara, bahkan memang secara khusus mengisi keanggotaannya, hal mana tentunya membawa berbagai perbedaan, baik visi maupun misi, terutama jika dilihat daripada kepentingan yang diwakilinya kemudian. Jika saja nanti dalam kenyataannya terjadi perbedaan pendapat, terutama berkaitan dengan pemeriksaan maupun untuk memutuskan dalam Majelis Kehormatan Hakim tersebut, sehingga permusyawaratan tidak mungkin tercapai, maka keputusan akan diambil kemudian dengan suara terbanyak (voting). Di mana tentunya dengan jumlah anggota Komisi Yudisial yang lebih banyak dalam Majelis Kehormatan Hakim akan membawa keuntungan tersendiri ketimbang Mahkamah Agung. Hal ini sangat jelas diatur kemudian dalam ketentuan Pasal 22F ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011, bahwa: Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana
I Gusti Ngurah Santika, SPd
371
dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak (kursif penulis). Keputusan dari Majelis Kehormatan Hakim adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat, yang tentunya wajib untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dengan diberikan batas tenggang waktu sampai 30 hari harus sudah dilaksanakan, terhitung sejak diputuskan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Dengan demikian kebebasan Hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan Kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi ia dibatasi oleh rambu-rambu berikut, akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi pengawasan (kontrol) (Lotulung,2003;8). Tanpa adanya rambu-rambu yang dipandang jelas bagi hakim dalam menegakan hukum dan keadilan, yang terjadi adalah tindakan arogansi pengadilan, hal mana tercermin dalam putusan hakim, yang tentunya berpotensi untuk menindas hak asasi manusia, padahal sejatinya merupakan suatu tugas hakim untuk melindunginya. Oleh karena itu, kedudukan Komisi Yudisial ini ditentukan dalam UUD 1945, sebagai lembaga negara yang mandiri, karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan prilaku hakim. Sehingga untuk itu, Erwiningsih (2004;140) berpendapat bahwa sistem politik yang demokratis menuntut suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka yang tentunya juga memiliki kualitas dan pengawasan yang baik. Walaupun lembaga yudikatif, dalam hal ini adalah MA, memiliki sistem pengawasan dari dalam terhadap hakim-hakim, namun tentunya tidak akan lebih efektif, jika saja pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga eksternal, dikarenakan tentunya terpisah dari yang diawasi oleh lembaga pengawasnya, terkait dengan struktur organisasinya. Untuk maksimalnya pengawasan terhadap perilaku hakim, guna mencegah penyalahgunaan wewenangnya, maka diperlukan lembaga yang tersendiri, di samping bersifat mandiri, agar pengawasannya kemudian dapat dilakukan dengan efektif. Bahwa terbukti hanya dengan pengawasan internal tidaklah cukup untuk melakukan pengawasan terhadap hakim. Oleh karena itu, perlu diadakan lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial. Selanjutnya peranan Komisi Yudisial melakukan pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan secara mandiri, karena tidak mempunyai hubungan administrasi, struktural, kolega maupun secara psikologis yang selama ini menjadi hambatan di dalam dalam melaksanakan pengawasan di dalam instansi atau lembaga sendiri. Hal ini tidak hanya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
372
dialami di Indonesia tetapi di negara-negara asing seperti Amerika dan Australia (Azhar,2005;22). Sehingga, kekuasaan kehakiman sebagai cermin dari negara hukum, yang merupakan salah satu wujud daripada kedaulatan rakyat, benar-benar dapat berdaulat, bahkan bisa menjadi penentu dalam mengambil keputusan, tentunya keputusan yang diambil selalu mencerminkan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, pencari keadilan pada khususnya. Untuk itu, diperlukan kerangka yang jelas bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangannya, yaitu untuk menjaga dan menegakan kehormatan hakim, sehingga nantinya mampu menciptakan peradilan terpercaya dan modern. Untuk sekarang ini, dalam melaksanakan tugasnya, baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial telah memiliki pijakan yang jelas dalam kerangka norma, sebagai pedoman utama untuk menjaga dan menegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kerangka pedoman sebagaimana dimaksud di atas adalah sesuai dengan norma dan peraturan perundangundangan, selain itu juga harus berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim yang memang menjadi pedoman dalam melakukan tugasnya. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial (Pasal 43 UU No. 48 Tahun 2009). Dengan demikian, jika hakim suatu saat diduga telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim, maka dalam hal ini dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Adanya kata dan/atau menunjukan, bahwa dapat saja kemudian hakim yang diduga telah melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, diperiksa kemudian oleh kedua lembaga negara tersebut, yakni Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sedangkan sesuai dengan norma tersebut di atas, dapat juga nantinya dalam melakukan pemeriksaan tersebut, dapat dilakukan secara sendirian ataupun terpisah sebagaimana dimaksud di atas, yaitu Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial, hal mana adalah tergantung dari kebutuhan dan ketentuan yang diatur kemudian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 berkaitan dengan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakan kehormatan hakim, ditentukan bahwa.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
373
1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim (kursif penulis). Oleh karena beratnya tugas yang diemban oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Yudisial, sehingga untuk itu diperlukan orang-orang yang benar-benar mampu, serta memiliki komitmen kuat untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim. Bahkan, dalam ketentuan Pasal 26 huruf f UU No. 18 Tahun 2011, berkaitan dengan syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Yudisial, yaitu hanya orang yang berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Ini membuktikan bahwa peradilan di Indonesia masih harus diperbaiki terus menerus, namun pekerjaan ini bukanlah sesuatu yang mudah begitu saja dilakukan, seperti membalikan telapak tangan. Tanpa adanya komitmen yang kuat, maka niscaya banyak kesulitan yang kemudian akan ditemui, hal ini tidak lain dikarenakan untuk mengawasi suatu perilaku hakim, yang dalam melaksanakan tugasnya telah ditentukan merdeka dan tidak boleh di intervensi, menjadikan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang, tentunya akan selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya agar jangan sampai kemudian pengawasan yang dilakukan oleh KY ternyata memasuki ranah yudikatif, dan pada akhirnya dikatakan bahwa KY telah melakukan campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari campur tangan dari luar termasuk KY. Walaupun untuk sekarang ini, Komisi Yudisial telah ditentukan dalam melakukan tugasnya, terutama untuk rangka menjaga dan menegakan kehormatan hakim dapat menganalisis putusan hakim. Hal ini sangat jelas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Dengan demikian, kewenangan Komisi Yudisial dalam menganalisis
I Gusti Ngurah Santika, SPd
374
putusan hakim, hanyalah sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi terhadap hakim, bukan untuk memberikan sanksi. Hal ini tidak lain didasari bahwa putusan yang diambil oleh hakim adalah bebas, yang mana adalah sesuai dengan sifat daripada kemerdekaan hakim, di dalam menjalankan tugas. Jadi, jika Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga dan menegakan keluhuran, martabat serta perilaku hakim, melakukan analisis terhadap putusan hakim, maka dapat dikatakan bahwa Komisi Yudisial telah memasuki ranah kekuasaan yudikatif. Kewenangan untuk mengalisis putusan peradilan hanya boleh dilakukan oleh badan peradilan yang lebih tinggi, untuk kemudian dapat saja membatalkan putusan peradilan yang ada di bawahnya. Untuk itulah tugas yang diemban oleh Komisi Yudisial semakin berat, dalam kaitannya untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim. Terutama dalam hal ini adalah untuk mengalisis kualitas daripada putusan-putusan hakim dalam rangka menentukan dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Dengan demikian, tentunya diperlukan orang-orang yang benar-benar mampu dalam menyelesaikan semua persoalan, khususnya berkaitan dengan menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim. Dalam UUD 1945 tepatnya ketentuan Pasal 24B ayat (2) telah atur dengan jelas untuk menjadi anggota KY tentunya harus mempunyai pengalaman di bidang hukum, di samping itu juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Sehingga, nantinya untuk menjaga keluhuran, kehormatan martabat dan prilaku hakim harus dilakukan oleh orang yang benar-benar memiliki integritas, serta kepribadiannya tidak tercela. Ketentuan yang sama kemudian dapat dijumpai kembali dalam ketentuan Pasal 26 huruf g UU No. 18 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa calon anggota Komisi Yudisial harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Sebab jika orang-orang yang tidak memiliki integritas dan kepribadian tercela menjadi pengawas untuk menjaga dan menegakan keluhuran, kehormatan martabat serta prilaku hakim, yang terjadi adalah tindakannya dapat saja membuat peradilan menjadi semakin tidak baik. Dengan kata lain, bukan menjaga yang dilakukan namun perbuatan yang malah dapat menjatuhkan serta melecehkan keluhuran, kehormatan martabat hakim, hal mana tentunya bertentangan dengan tugas yang seharusnya dijalankannya. Sehingga perlulah kemudian Komisi Yudisial, sadar akan hak dan kewajibannya untuk dapat menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan prilaku hakim. Bahkan dalam ketentuan Pasal 20A huruf a dan d UU No. 18 Tahun 2011, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Komisi Yudisial wajib (a) menaati peraturan perundang-undangan, (d) menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
375
diberikan kepada Presiden oleh UUD 1945, namun perlulah kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR. Adanya ketentuan tersebut, tidak lain agar dalam melakukan tugasnya Komisi Yudisial benar-benar independen/mandiri, sehingga tidaklah dapat dipengaruhi oleh kekuasaan yang datang dari luar. Terutama oleh kekuatan politik yang ingin menekan kekuasaan kehakiman, dengan jalan mengawasi dan menegakan, yang hanya sebenarnya bertujuan untuk menjatuhkan dan melecehkannya. Oleh karena itu, sebaiknya KY lebih dekat dengan kekuasaan kehakiman, bukannya dengan lembaga eksekutif maupun legislatif yang berpotensi menjadikan KY sebagai alat politik dari kedua lembaga negara tersebut untuk menekan hakim dalam menjalankan tugasnya yang sebenarnya merdeka, khususnya untuk mengambil keputusan. Sehingga bisa saja berpotensi memandulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum yang pada akhirnya dapat menciptakan keadilan. Dengan keterlibatan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota KY, diharapkan nantinya KY benarbenar independen dalam melaksanakan tugasnya, sehingga secara tidak langsung KY juga merupakan salah satu lembaga negara yang merupakan pelaksana kedaulatan rakyat, karena anggota KY tidaklah dapat diberhentikan seenaknya oleh Presiden tanpa mendapat persetujuan daripada DPR. Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim atau boleh dikatakan keberadaan Komisi Yudisial ini sebagai pengontrol atau pengawasan terhadap hakim, disamping berfungsi untuk merekrut hakim agung (Harun,2008;34). Institusi pengawasan yang dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung, memberikan ruang penyerapan aspirasi masyarakat di luar struktur resmi untuk dapat terlibat dalam proses pengangkatan para hakim agung serta dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran etika (ICC UIN,2010;74). Oleh sebab itu, sebagai sebuah lembaga negara, maka kedudukan KY tidaklah berada di bawah MA maupun MK, tetapi tugas dan wewenangnya tetaplah bersifat penunjang bagi kekuasaan kehakiman. Terkait dengan hal tersebut, Argama (2006;21) kemudian berpendapat sama tentang kedudukan KY, yaitu sebuah lembaga negara bantu (state auxiliary institutions) yang memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun, meskipun sebagai lembaga penunjang, jika dilihat bahwa KY merupakan lembaga yang mandiri dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat dikatakan KY memiliki peranan yang sangat strategis untuk tegaknya keluhuran, kehormatan martabat serta perilaku hakim yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
376
pada akhirnya bermuara pada tegaknya hukum dan keadilan. Komisi yudisial bukan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman seperti MA dan MK, melainkan hanya sebagai lembaga yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman atau dapat disebut sebagai supporting institution. Akan tetapi di sini, dapatlah ditegaskan bahwa sebagai lembaga pengawas eksternal kedudukan, KY bukan supporting melainkan dapat juga disebut sebagai main institution. Dengan demikian, pembedaan yang digunakan untuk membandingkan antara supporting institution dengan main institution adalah berkaitan dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Terkait dengan pengaturan KY, kedua versi ketentuan tersebut, yaitu UUD 1945 dan versi UU tentang Komisi Yudisial, memang jelas satu sama lain berbeda. Pertama, dalam undang-undang, Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung .. Kedua, dalam undang-undang dinyatakan, Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta menjaga prilaku hakim. Sedangkan, dalam UUD 1945 menyatakan, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Asshiddiqie,2006;193). Dari segi pertama, Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 memang menentukan bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dalam ketentuan konstitusi itu, tidak dibatasi dan juga ditentukan bagaimana dan ke mana usul tersebut disampaikan oleh Komisi Yudisial (Asshiddiqie,2006;194). Namun, menurut pendapat penulis, kuranglah tepat pendapat yang telah dinyatakan oleh Asshiddiqie, hal mana dikarenakan dalam ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa Calon hakim agung diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Jadi walaupun dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, tidak dinyatakan kemana arah untuk selanjutnya mengajukan calon hakim agung, namun dapatlah kemudian ditemukan kembali dalam ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dan selanjutnya dijabarkan kembali dalam bentuk peraturan yang lebih rendah, yaitu UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terutama dalam ketentuan Pasal 13. Artinya disini bahwa ketentuan terakhir berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengangkatan hakim agung, yang dikarenakan posisi Komisi Yudisial hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung bukan mengangkat hakim agung. Pernyataan berkaitan dengan jumlah calon hakim agung yang diusulkan oleh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
377
KY ke DPR memang tidak ditentukan, namun untuk diangkat maka diperlukan persetujuan dari DPR, sehingga semuanya tergantung daripada kebutuhan jumlah yang diperlukan kemudian barulah diusulkan oleh KY untuk mendapatkan persetujuan dari DPR, yang tentunya dalam hal ini perlu diatur kembali dalam undang-undang. 8. Mahkamah Konstitusi (MK) Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan (Asshiddiqie,2009;301). Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special Tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (modern nation- state), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi (Siahaan dalam Santika,2012;172-173). Pengujian ini biasanya disebut judicial review (Mahmud MD,2009;257). Dalam Blacks Law, Judicial review diartikan sebagai power court to review decision of another department or level government (Fatmawati,2005;8). Yudicial review adalah fenomena yang beriringan dengan perkembangan ide negara demokratis (Isra,2010;294). Sejarah modern judicial review, yang merupakan ciri kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung, dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai penerimaan yang luas (Siahaan,2010;3). Kendati pada saat itu konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan yudicial review kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskannya untuk senantiasa menegakan konstitusi, Marshal menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi (Mahkamah Konstitusi,2010;1). Argumentasi yang mendasari kewenangan pengadilan untuk melakukan pengawasan konstitusi tersebut memberikan dorongan bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan judicial review (Fatmawati,2005;75). Sudah selayaknya menjadi wewenang para hakim untuk memutuskan apa arti hukum (Wheare,2005;152). Yudicial riview itu lahir ke dalam tatanan hukum Amerika Serikat lewat putusan hakim (Yusdiansah,2010;65). Dapatlah katakan kemudian bahwa yudicial riview merupakan konvensi ketatanegaraan tidak lain, karena kebutuhan akan ketentuan-ketentuan untuk pelengkap (supplement) rangka hukum konstitusi (Suny,1986;37). Akan tetapi para pendiri pasti memahami bahwa pengadilanlah yang akan melakukan wewenang itu (Rodee,2011;305). Sehingga secara implisit UndangUndang Dasar menetapkan adanya suatu pengadilan federal yang berhak mengadili semua
I Gusti Ngurah Santika, SPd
378
persoalan konstitusional (Budiardjo,2010;278). Lagi pula dengan tiadanya kontrol undang-undang dasar sama sekali akan kehilangan azasnya (Soehino,1983;269). Dengan hak yudicial review ini Mahkamah Agung Amerika Serikat berhak untuk menguji apakah suatu peraturan, baik negara bagian maupun federal, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat atau tidak (Anthony,1984;5). Kekuasaan dimaksudkan agar konstitusi merupakan perjanjian antara negara-negara yang bergabung ini tidak digerogoti baik melalui Undang-Undang Federal maupun melalui Undang-Undang Negara bagian(Soemantri,2006;119). Hal mana akan mengakibatkan tidak dapat dijalankannya undang-undang atau kebijaksanaan pemerintah yang bersangkutan (Hartono,1982;26). Karena sesuai dengan pendapat Montesquieu (2011;363) yang menyatakan jika terdapat undang-undang yang tak bermanfaat, lebih baik disingkirkan saja karena hanya akan memperlemah hukum. Pengaruh Mahkamah Agung demikian besar sehingga pernyataan tidak konstitusional dianggap mengikat pada badan legislatif dan badan eksekutif (Anwar,1998;125). Dapat dikatakan bahwa di Amerika Serikat kedudukan lembaga yudikatif terhadap lembaga legislatif adalah kuat dengan wewenang supreme court di sana menyatakan suatu undang-undang tidak sah dan tidak berlaku karena dianggap bertentangan dengan konstitusi (Prodjodikoro,1981;91). Tidak lain dikarenakan bahwa undang-undang dasar modern juga memuat gronrechten, scheiding van machten agar terdapat een system van checks and balances (Djokosoetono,2006;89). Memang, hakim federal tidak dapat menghapuskan undang-undang tersebut tetapi dia harus menyatakan undang-undang itu tidak sah secara legal di hadapan pengadilan untuk semua kasus yang timbul karenanya (Strong,2005;386). Dengan demkian dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung federal merupakan pengadilan tertinggi untuk menyelesaikan persoalan konstitusional (Budiardjo,2008;278). Dengan tradisi yang demikian, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menciptakan dasar-dasar bagi terbentuknya satu sistem, mekanisme, atau institusi baru dalam praktek, yaitu perlindungan hukum atas konstitusionalitas (judicial protection of constitutionality) (Asshiddiqie,2010;26). Oleh karenanya dapat dikatakan, bahwa Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan modern, bahkan menjadi dasar daripada terbentuknya Mahkamah Konstitusi, yang juga tentunya memiliki tugas sama dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pada hakekatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (the guardion of the constitutions) (Tutik,2008;260). Mengapa sistem pengujian undang-undang di Amerika Serikat bukannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang karena itu diberikan sebuah hak untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Federal? Di dalam tradisi common law dan sistem konstitusi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
379
Amerika Serikat (AS), lembaga MK yang tersendiri tidak dikenal, tetapi fungsinya langsung menjadi kewenangan Mahkamah Agung (supreme court) yang disebut the guardion of American Constitution (Latif,2009;183). Sedangkan Asshiddiqie (tt;193) menyatakan bahwa sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Perkembangan selanjutnya adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) yang terpisah dengan Mahkamah Agung yang diprakarsai oleh Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari Universitas Wina (Vina) di Austria yang mengusulkan dibentuknya sebuah badan yang diberi nama Verfassungsgerichtshoff sehingga oleh para sarjana menyebut Mahkamah Konstitusi Austria disebut sebagai The Kelsenian Model (Asshiddiqie,2010). Sebaliknya justru bangsa Amerika Serikatlah yang pertama mengembangkan mekanisme judicial Riview atas undang-undang buatan Konggres, dimulai dengan putusan atas kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803 (Asshiddiqie,2006;3). Walaupun dalam kenyataannya bahwa fungsi dan mekanisme (constitutional riview of laws) telah lama diterapkan dalam praktek (Latif,2009). Pada hakekatnya, fungsi utama MK adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (the guardian of the constitution) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (the interpreter of the constitution) (Asshiddiqie, 2004;5-6). Bahkan, dapat dikatakan, sejak umat manusia berkenalan dengan gagasan Mahkamah Konstitusi pada tahun 1920-an, luas sekali pengaruhnya terhadap perkembangan teori dan praktik dalam hukum tata negara seluruh dunia (Asshiddiqie,2006;322). Berbeda dengan keadaan di Belanda, maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas Soepomo (1988;71) kemudian berpendapat bahwa pengujian sahnya undang-undang (materiele toetsingsrecht) tidak diizinkan kepada pengadilan, berdasarkan ketentuanketentuan dari Pasal 124 (2) UUD Belanda, bahwa undang-undang itu tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya pengadilan berhak menguji sahnya semua peraturan yang lain. Berdasarkan hal tersebut, Kansil dan Christine (2002;152) menyatakan bahwa ketentuan ini mengandung larangan bagi hakim maupun bagi administrasi negara. Sekalipun hakim atau administrasi negara yakin bahwa isi dan tujuan sesuatu undang-undang bertentangan dengan isi dan tujuan undang-undang dasar, masih juga mereka tidak berwenang menyatakan tidak-berlakunya undang-undang itu. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hakim maupun administrasi negara tidak boleh menguji isi undang-undang itu pada undang-undang dasar. Adanya larangan pengujian undang-undang terhadap UUD, karena menurut Aziz (2010;114) bahwa hal ini menggambarkan bahwa UU merupakan cerminan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
380
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan ada parlemen (supremasi parlementer). Pembentuk undang-undang sendiri adalah satu-satunya yang berhak untuk menentukan, adakah peraturan yang dikehendaki sesuai dengan Undang-Undang Dasar (Apeldoorn,2011;83). Belajar dari pengalaman masa lalu, kalau hanya mengandalkan legislative review hasilnya tidak begitu menggembirakan karena tidak menampung derasnya aspirasi keadilan yang hidup dan berkembang di tengah aspirasi masyarakat (Yasabari,1984;62). Dasar pemikiran tersebut tidak lain dikarenakan bahwa kecil kemungkinan suatu lembaga untuk menghapus suatu produk yang dibuatnya sendiri dengan dalih bertentangan dengan UUD. Terkait dengan pengujian undang-undang dapat dinyatakan, dengan adanya MK ini yang dulunya merupakan pandangan klasik Montesquieu yang menyatakan bahwa hakim hanyalah corong dari undang-undang yang tidak dapat mengubah atau menambah undangundang (Mertokusumo dan Pitlo,1993;6), hal ini mengandung arti bahwa tugas kekuasaan yudisial adalah untuk melaksanakan perintah undang-undang terhadap suatu kasus atau peristiwa konkret (Sibuea,2010;111), namun untuk sekarang hakim konstitusi dapat membatalkan undang-undang, jika dipandang bertentangan dengan undang-undang dasar. Karena itu, di samping berfungsi sebagai pengawal UUD, Mahkamah Konstitusi juga biasa disebut sebagai the sole interpreter of the constitution (Asshiddiqie,2006;153). Dibentuk lembaga pengadilan untuk melakukan pengujian UU adalah dalam rangka mengimbangi kekuasaan legislatif, khususnya pembuatan UU agar nantinya tidak bertentangan dengan UUD. Undang-undang yang dibuat perlu diuji kembali oleh lembaga peradilan, dikarenakan menurut Isra (2010;121-122) bahwa sebagai hasil dari sebuah proses politik, John Agresto mengemukakan, tidak tertutup kemungkinan munculnya undang-undang yang opresif dan atau despotik. Lebih lanjut, Rozali (2009) menyatakan bahwa undang-undang yang dihasilkan sering tidak memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Dalam hal ini tentunya akan merugikan daripada rakyat, yang sebenarnya oleh konstitusi telah ditentukan sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya, sehingga tindakan wakil rakyat seharusnya selaras dengan kehendak yang diwakilinya, namun dalam kenyataannya bisa saja terjadi sebaliknya. Untuk menjamin hal tersebut, maka keberadaan MK merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, Asshiddiqie dan Safaat (2006;139) menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu hukum itu konstitusional atau tidak dan tidak memberlakukannya jika sesuai dengan pendapat organ ini tidak konstitusional. Dengan demikian, hendaknya bermaksud untuk meletakan konstitusi sebagai aturan paling tinggi, tentunya tidak boleh di simpangi oleh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
381
peraturan yang kedudukannya lebih rendah. Untuk itu kemudian dibutuhkanlah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk menjamin tegaknya konstitusi, tanpa adanya lembaga tersebut konstitusi tidak akan dapat ditegakan. Karena jika tidak terdapat lembaga negara yang ditunjuk secara langsung oleh konstitusi, untuk menjamin agar tidak dilanggarnya kaidah-kaidah konstitusi, maka konstitusi hanyalah sebagai hiasan ketatanegaraan palsu. Lembaga yang kemudian dimaksudkan adalah Mahkamah Konstitusi (constitutional court), yang bertugas menyesuaikan undang-undang dengan konstitusi agar selaras, hal mana dikarenakan bahwa undang-undang sendiri merupakan sebuah produk politik. Lebih tegas lagi berkaitan UU sebagai produk politik, karena dibentuk oleh badan politik, Marzuki (2007;5) berpendapat bahwa: Tatkala suatu undang-undang dipahami selaku produk politik karena di desain, dirancang oleh body politics, seperti halnya dengan DPR dan Presiden maka kadangkala dalam undang-undang terdapat kepentingan para politik (de wet gevers) di kala proses pembentukan undang-undang, yang bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Undang-undang semacamnya kelak ternyata ditemukan pada muatan substansi undang-undang yang dipandang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demkian, tidak tertutup kemungkinan adanya suatu undang-undang yang dibuat oleh lembaga politik, namun dalam kenyataan semangat yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan jiwa konstitusi, yang sebenarnya memberikan atribusi berupa kewenangan untuk mengaturnya lebih lanjut, dengan ataupun dalam bentuk undangundang. Bahkan, jika hukum dalam arti undang-undang yang dibuat oleh legislatif sudah bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dipastikan kemudian bahwa undang-undang tersebut, akan jadi merugikan rakyat banyak pula. Tidak lain disebabkan, bahwa konstitusi itu sendiri merupakan perjanjian rakyat yang kedudukannya tertinggi, bahkan hak-hak rakyat telah diletakan di dalamnya sebagai wujud perlindungan yang nantinya akan diberikan konstitusi, namun ditentukan kemudian untuk diatur dengan peraturan di bawahnya lebih lanjut baik dalam/dengan bentuk undang-undang. Untuk itu menurut, Safaat (2011;42) bahwa hukum yang dibuat sebagai dasar keberadaan negara tersebut harus demokratis, yaitu sesuai dengan tuntutan masyarakat. Namun, tidak seperti keadaan normatifnya, jika dilihat dari sisi kenyataannya (sein) maka undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakan sebuah produk politik. Undang-undang adalah produk politik, sebagai produk politik banyak kepentingan-kepentingan politik yang terdapat di dalamnya, kepentingan-kepentingan itu bergulat agar selanjutnya dapat menjadi sebuah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
382
kebijakan, yang pada akhirnya mengikat rakyat dan juga tentunya bersifat memaksa. Yang berbahaya adalah jika suatu kepentingan politik yang tertanam di dalamnya, ternyata kemudian bertentangan dengan konstitusi, karena pada dasarnya dalam konstitusi telah adanya jaminan hak-hak konstitusional rakyat, untuk itulah perlu kembali mengidentifikasikan suatu undang-undang yang bisa saja nantinya akan merugikan rakyat dengan lebih cermat lagi. Analisis kritis terhadap produk perundang-undangan (critical legal analisys) tidak hanya berusaha untuk menelaah muatan materiil dari produk perundang-undangan melainkan juga bertujuan untuk mengidentifikasikan kepentingan yang tersembunyi (intention political hidden)(Rahayu,2007;289). Mungkin saja kepentingan-kepentingan tersembunyi tersebut, berpotensi untuk merugikan kepentingan banyak orang, yang pada dasarnya jelas-jelas dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, jelaslah bahwa posisi Peradilan Konstitusi (constitutional judiciary) dalam struktur masyarakat normatif menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari (Stefanus,2009;19). Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya peradilan konstitusi, produk politik berupa undang-undang dapat dihasilkan dengan lebih memihak kepada rakyat, sehingga tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang hanya menguntungkan antara pihak eksekutif dan legislatif, selaku organ yang ditugaskan untuk membuatnya. Lebih lanjut terkait dengan hukum yang berbentuk undang-undang, hal mana dibentuk oleh eksekutif dan juga legislatif, Cassese (2005;29) menyatakan dengan tegas bahwa: Jika ada yang bertanya bagaimana semuanya itu dapat berfungsi dalam praktik maka kita langsung menyadari bahwa teks-teks itu semuanya sangat mungkin dimanipulasi, karena teks-teks memberikan sejumlah peluang dan jalan keluar bagi badan-badan kekuasaan politik. Yang disebut kemudian ini berhak menentukan batas-batas kebebasan, menentukan apa yang dapat membahayakan masyarakat, bila saatnya tatanan umum secara absah dapat membatasi kebebasan, dan seterusnya. Satusatunya pembatasan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan politik adalah Hukum. Kenyataan bahwa semua putusan seperti itu bukan diambil oleh kekuasaan eksekutif tetapi oleh badan badan legislatif, dianggap merupakan penjagaan terhadap kesewenang-wenangan. Namun apabila kita teliti secara lebih mendalam, kita menyadari bahwa itu tidak memperlihatkan bagaimana hukum itu akan dibuat: meskipun semuanya menekankan bahwa semua warga negara harus ikut serta dalam pembuatan undang-undang, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakilwakil mereka, namun semuanya tidak menjelaskan syarat-syarat minimum yang harus
I Gusti Ngurah Santika, SPd
383
dipenuhi agar hukum itu benar-benar menjadi kehendak rakyat sesungguhnya (kursi penulis). Dari sudut pandang teori kelompok, pengesahan undang-undang melalui badan legislatif melulu dilihat sebagai perebutan pengaruh antar kelompok yang berkompetisi, yang masing-masingnya berusaha memajukan kepentingan sendiri (Rodee dkk,2011;15). Hal ini membuktikan bahwa produk hukum yang dibuat oleh badan legislatif, tidaklah sepenuhnya dapat mewakili kehendak rakyat, bahkan bisa jadi berlawanan dengan kemauan rakyat itu sendiri yang seharusnya diwakili. Dengan demikian, akan berpotensi melanggar hak-hak rakyat yang ditetapkan oleh konstitusi, padahal konstitusi itu sendirilah yang sebenarnya merupakan kehendak rakyat. Bukannya undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dengan eksekutif lebih tinggi kedudukannya, karena dapat dipastikan bahwa nilai konstitusi lebih tinggi kedudukannya daripada undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga negara yang diberikan tugas untuk melindungi hak-hak rakyat dengan menjungjung tinggi supremasi konstitusi dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga politik, yang sebelumnya diberikan mandat oleh rakyat itu sendiri. Bahkan hendaknya undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif harus mendasarkan diri kepada keadilan, di samping tentunya juga berdasarkan nilai-nilai konstitusi. Hal ini sesuai dengan pendapat Prodjodikoro (1981;33) yang menyatakan bahwa badan legislatif dalam merancangkan dan membikin undang-undang harus memperhatikan keadilan. Jangan sampai, suatu undang-undang mengandung peraturan yang bersifat diskriminatif dan menguntungkan satu pihak saja yang tidak seimbang dengan apa yang dibagikan kepada pihak lain. Dari segi konsepsinya, apa yang terkandung dalam perkataan constitutional review itu jelas berkaitan erat dengan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the constitution). Prinsip ini dalam perkembangan sejarahnya berhadap-hadapan dengan doktrin kedaulatan parlemen (sovereignity parliament) atau prinsip supremasi parleman yang berdaulat. Dalam sistem pengujian konstitusionalitas (constitutional review), terkandung pengertian bahwa yang supreme itu adalah konstitusi (the idea of the supremacy of the Constitution), bukan parlemen. Untuk menjamin supremasi hukum tertinggi tersebut atau the supreme law of the land, diperlukan lembaga tersendiri yang terbebas dari pengaruh cabang kekuasaan legislatif ataupun eksekutif (Asshiddiqie,2010;30). Dapat dikatakan bahwa perkembangan ke arah terbentuknya Mahkamah Konstitusi, merupakan kelanjutan dari perkembangan kedaulatan rakyat yang kemudian terwujud dalam bentuk lembaga legislatif. Di mana diawali daripada berpindahnya sebagian kekuasaan raja ke badan parlemen dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
384
pembuatan peraturan yang mengikat misalnya undang-undang, kemudian disusul pula dengan berpindahnya kekuasaan raja untuk mengadili ke tangan yudisial, yang kedudukannya berdiri sendiri, bahkan kemudian membalutnya dengan kedaulatan hukum. Diadopsinya prinsip pengujian konstitusional (constitutional review) tersebut berkaitan pula dengan pengertian bahwa kekuasaan negara harus dipisah-pisahkan secara horizontal (horizontal separation of power) antar berbagai lembaga negara (state organs) yang sederajat satu sama lain bersifat saling mengendalikan (Asshiddiqie,2006). Adanya Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk upaya dalam mengimbangi atas kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif (Hamidi dan Lutfi,2010;31). Prinsip inilah yang biasa disebut cheks and balances. Di samping itu, pengujian konstitusional (constitutional review) juga dikaitkan dengan berlakunya prinsip pemisahan kekuasaan secara vertical (vertical separation of power) sebagaimana dimaksud di atas. Selain itu, dianutnya sistem pengujian undang-undang adalah merupakan suatu konsekuensi bagi negara yang menganut prinsip hierarki norma, seperti teori hierarki norma dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Mengenai norma dalam sistem norma yang dinamik, Hans kelsen mengajarkan, bahwa suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, norma ini dibentuk oleh norma lebih tinggi, dan demikian hal itu seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi lagi yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi melainkan diperkirakan (Presupposed, voorondersteld) atau ditetapkan terlebih dahulu voraugezetzt keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat sendiri. Kelsen menamakan norma tertinggi ini Grunorm, Basic Norm (Norma Dasar). Hans Nawiasky mengatakan, norma tertinggi dalam negara sebaiknya tidak disebut Staatgrunorm melainkan Staatfundamentalnorm, norma fundamental negara. Pertimbangannya ialah karena Grunorm dari suatu tatanan norma pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedang norma tertinggi suatu negara mungkin berubah-ubah oleh pemberontakan, coup detat, putsch, anschluss, dan lain sebagainya (Atammimi, 1990;358-359, Indrati,2007;48). Oleh karena itu, dapatlah dikatakan kemudian bahwa peraturan itu mempunyai hierarchis (tingkatan), dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya (Soemitro,1992;35). Hal mana adalah sesuai dengan adagium lex superior derogate legi inferiori, jika dua (norma) hukum bertentangan, yakni antara hukum yang kedudukannya lebih rendah dengan hukum yang kedudukannya lebih tinggi, maka hukum yang kedudukannya lebih tinggi mengalahkan hukum yang kedudukannya lebih rendah. Adanya ketentuan tersebut merupakan asas hukum yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
385
terjelma di belakang setiap sistem hukum peraturan perundang-undangan. Jadi, asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak (Mertokusumo,1996;33). Bahkan, dikatakan bahwa azas hukum merupakan jantungnya hukum, dengan adanya azas hukum dimungkinkan adanya peyimpangan-penyimpangan hukum dikarenakan terjadinya bentrokan antara peraturan-peraturan hukum yang konkrit, sehingga membuat hukum semakin luwes. Fungsi daripada asas hukum setidaknya untuk menjaga ketaatan asas, menyelesaikan pertentangan yang terjadi dalam sistem hukum, dan sebagai rekayasa sosial baik dalam sistem hukum mupun dalam sistem peradilan. Selain itu, sebenarnya masih ada asas-asas yang berlaku lainnya dalam ilmu hukum seperti lex posteriori derogate legi priori (aturan hukum yang baru menyampingkan aturan hukum yang lama, dalam mengatur mengenai hal yang sama), asas legalitas (nulum delicticum nulla poena sine pravea lege poenali (Pasal 1 ayat KUHP), asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum atau hukumnya kurang jelas (ius curia novit), ketentraman masyarakat harus dipulihkan kembali (restutio in integrum), eidereen wordt geacht de wette kennen, gogattionis poenam nemo patitur, lex dura sed temen/lex dura secta mante scripta, lex minimum cogit ad imposibilia dll. Untuk lebih jauh lagi mengetahui tentang lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi, khususnya di Indonesia, maka perlulah diceritakan kembali sedikit terkait dengan sejarah pada awal mulanya perdebatan, pada saat pembahasan konstitusi pertama, khususnya berkaitan dengan perdebatan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dilanjutkan kembali dalam sejarah perjalanannya yang ternyata lembaga ini sangat dibutuhkan oleh republik ini, namun dikarenakan kekuasaan yang sifatnya otoritarian, sehingga pada akhirnya pemikiran terkait dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi terhenti untuk waktu sejenak. Kemudian kesempatan untuk membentuk lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi (constitutional court) baru datang kembali, bahkan mewarnai perdebatan di MPR, hingga akhirnya kemudian benar-benar di adopsinya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pelindung konstitusi. Untuk itu, baiklah kita telusuri sedikit sejarah berkaitan dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini. Untuk di Indonesia, sejarah terkait keberadaan hak untuk menguji UU terhadap UUD di Indonesia sebenarnya dapat telusuri lebih jauh, dengan adanya pendapat yang diusulkan oleh Moh.Yamin dalam sidang BPUPK, yang ketika itu menyatakan bahwa Balai Agung janganlah saja melaksanakan bagian kehakiman, tetapi juga hendaklah menjadi badan yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
386
membanding, apakah Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak melanggar Undang-Undang Dasar republik atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syariah agama Islam (Setneg,1995;299) (kursif penulis). Namun, dalam perjalanannya dalam kenyataannya pendapat berupa usul yang diajukan oleh Moh. Yamin tersebut tidaklah disetujui oleh Soepomo dengan alasan sebagai berikut. Kecuali itu tuan Paduka Ketua, kita dengan terus terang akan mengatakan, bahwa para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini, dan Tuan Yamin harus mengingat juga bahwa di Austria, Ceko-Slowakia dan Jerman waktu Weimer bukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan special, constitutioneel-hof, suatu pengadilan spesifiek- yang melulu mengerjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi, buat negara yang muda saya kira belum waktunya, mengerjakan persoalan ini (kursif penulis) (Setneg,1995;306). Selain masih minimnya tenaga ahli sebagaimana dimaksudkan di atas oleh Sopomo, bahwa Undang-Undang 1945 menurutnya tidaklah sama dengan negara lainnya yang pada dasarnya menganut sistem pemerintahan dengan memisahkan lembaga-lembaga negara (separation of power). Dikarenakan menurut Soepomo berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power), bukan pemisahan kekuasaan secara prinsipil di antara ketiga lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Montesquieu. Asshiddiqie dalam Arifin dan Wardi (2002;22) menyatakan bahwa kalau kita simak perdebatan para founding fathers kita dulu, mengapa MA tidak mempunyai kewenangan menguji UU, alasannya karena tidak ada separation of power, sehingga yang berhak menguji UU adalah lembaga yang membuatnya sendiri. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden), dalam arti yang dimaksud adalah review yang dilakukan kemudian oleh lembaga politik (political review or legislative riview), bukan yudicial review) yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Hal inilah yang kemudian terjadi di Belanda dengan menganut konsep kedaulatan rakyat, yang menempatkan kedudukan lembaga legislatif (parlemen) sebagai lembaga yang diberikan kedaulatan oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pengadilan tentunya tidak dapat menguji produk yang dibuat oleh lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Menurut Asshiddiqie (2012) terkait dengan adanya pernyataan Soepomo dikarenakan dalam sistem hukum Belanda ada doktrin bahwa undangundang memang tidak dapat diganggu gugat. Atas dasar itulah, Soepomo tidak menerima
I Gusti Ngurah Santika, SPd
387
ide untuk menguji undang-undang oleh Mahkamah Agung. Dalam sejarah perjalanannya ternyata kebutuhan akan adanya pelembagaan yudicial review sebenarnya sudah mulai nampak, terutama setelah jatuhnya Orde Lama dari tampuk kekuasaannya, yang pada saat pemerintahannya telah banyak melakukan tindakan-tindakan yang pada dasarnya bertentangan dengan UUD 1945, terutama dalam kaitannya dengan berbagai peraturan berupa penetapan-penetapan Presiden yang dibuat kemudian, dengan melabrak peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di atasnya, namun pada akhirnya tindakan-tindakan tersebut berakhir setelah kejatuhannya, yang sebelumnya ditandai dengan adanya Supersemar dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Pada awal Orde Baru, ketika sistem politik berjalan dengan langgam yang agak demokratis atau libertarian, masalah hak menguji materiil telah mulai diperdebatkan. Panitia ad hoc di MPRS pada tahun 1967-1969 telah merekomendasaikan beberapa hal termasuk diberikannya hak menguji materiil atas undang-undang kepada Mahkamah Agung. Rekomendasi yang disampaikan oleh panitia ad hoc II (membidangi reorganisasi pemerintahan ini) ditolak oleh pemerintah, seperti yang dialami oleh panitia ad hoc IV (yang membidangi dan menyusun Rancangan UU tentang Hak Asasi Manusia). Melalui Menteri Kehakiman, Oemar Seno Adji, pemerintah menolak hampir setiap premis dan kesimpulan panitia ad hoc II dengan menyatakan bahwa hanya MPR yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi dan MPR telah melakukan fungsi itu ketika memerintahkan kepada Presiden dan parlemen untuk mencabut beberapa produk peraturan perundangundangan yang diwariskan oleh demokrasi terpimpin (Mahmud MD,2011;350). Percobaan pertama yang kita adakan dapat dikatakan barulan muncul setelah era reformasi, yaitu dengan ditetapkannya Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 yang memberikan kepada MPR kewenangan aktif untuk menguji konstitusionalitas undangundang. Sebelum ini, prosedur pengujian (judicial review) oleh Mahkamah Agung hanya dibatasi pada objek peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, pengujian oleh Mahkamah Agung itu bukanlah pengujian mengenai konstitusionalitas, melainkan hanya pengujian legalitas peraturan perundang-undangan. Pengujian aktif (active review) yang seyogianya akan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan TAP MPR. No. III/MPR/2000 tersebut, sampai masa berlakunya ketetapan MPR tersebut berakhir, tidak pernah dilaksanakan, karena memang tidak ada mekanisme yang memungkinkannya secara teknis dapat dilaksanakan. Sekiranya pun hal itu dapat dilaksanakan, maka niscaya apa yang dilakukannya tidak dapat disebut dengan istilah judicial review, melainkan merupakan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
388
legislative review karena organ MPR itu sendiri termasuk cabang kekuasaan legislatif (Asshiddiqie,2010;ix-x) Dengan demikian, dalam sejarahnya perjalanan berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diperdebatkan dalam waktu yang cukup panjang. Sepanjang perjalanannya memang terlihat bahwa yang menjadi bahan perdebatan adalah masalah pengujian peraturan perundang-undangan, maupun lembaga yang nantinya berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Maka, yang baru menjadi kesepakatan pada waktu itu adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ternyata pengujian terhadap undang-undang barulah dapat dilaksanakan setelah era reformasi, namun dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, bukanlah dilakukan oleh Mahkamah Agung melainkan dilakukan oleh Mahkamah konstitusi, sebagai lembaga tersendiri yang kedudukannya terlepas dari struktural Mahkamah Agung, bahkan memiliki kedudukan yang sejajar sebagai sebuah lembaga negara yang sama-sama merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Terkait dengan di Indonesia, maka untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi (constitutional court) tidak terlepas dari adanya perubahan sistem ketatanegaran (constitutional system) yang terjadi dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR pada tahun 1999 hingga 2002. Menurut Jundiani (2010;2) bahwa perubahan tersebut juga mempertegas pembagian tugas antar lembaga negara dengan sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Terkait dengan pembentukan MK, Ginting (2006;63) menyatakan bahwa ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini. Perubahan tersebut dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan checks and balances yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia (Ashiddiqie,2004;3). Apa yang sebelumnya dinyatakan di atas, adalah merupakan bahan yang kemudian melatar belakangi serta membidani kelahiran MK di Indonesia. Supremasi hukum (supremacy of law) berpuncak pada konstitusi, yang dalam hal ini adalah UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, di samping juga berkedudukan sebagai hukum dasar (basic law). Dalam hal tersebut haruslah pula diperhatikan oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
389
selalu menjadikan UUD 1945 sebagai hukum dasarnya. Bahkan, dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan dengan tegas bahwa : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundangundangan (kursif penulis). Dengan begitu, dapat kemudian dikatakan bahwa UUD 1945 adalah untuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang pada gilirannya menjadi dasar dan sumber peraturan perundang-undangan bawahannya (Prakoso dan Murtika,1987;78). Dengan demikian, sebagai hukum dasar tentunya memiliki kekuatan yang lebih utama, dibandingkan dengan sumber hukum lainnya, seperti undang-undang yang merupakan perintah konstitusi untuk mengatur hal-hal yang memang tidak diatur di dalam konstitusi, untuk kemudian diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan yang kedudukannya lebih rendah. Namun, kemudian jika dibandingkan dengan kedudukan Pancasila, maka dapatlah dikatakan bahwa UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih rendah. Hal mana sebenarnya dapat kita ketahui dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus terkait dengan hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Apabila pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan Pancasila yang menciptakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (Staatfundamentalnorm) yang menjadi dasar dan sumber bagi Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (Verfassungnorm) yaitu batang tubuh (Indrati,2007;5859). Tidak lain, dikarenakan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum hukum (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011). Bahkan kata sumber hukum sering pula digunakan dalam beberapa arti, yaitu. a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya. b. Menunjukan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku : hukum Perancis, hukum Romawi. c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa masyarakat). d. Sebaga sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis dan sebagainya. e. Sebagai sumber terjadinya hukum : sumber yang menimbulkan hukum (Zavergen dalam Mertokusumo,1996;69, Ridwan HR,2011;55).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
390
Dalam kaitannya dengan sumber hukum, Apeldoorn (2011,73-78) menyatakan bahwa sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat dan formil. a. Sumber hukum dalam arti sejarah 1. Dalam arti sumber pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumen, inskripsi, dsb., darimana kita dapat belajar mengenal hukum sesuatu bangsa pada sesuatu waktu. 2. Dalam arti sumber-sumber darimana pembentuk undang-undang memperoleh bahan dalam membentuk undang-undang, juga dalam arti sistem-sistem hukum, darimana tumbuh hukum positif suatu negara. b. Sumber hukum dalam arti sosiologis Sumber hukum ialah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan-keadaan ekonomi, pandangan agama, saat psikologis. c. Sumber hukum dalam arti filsafat 1. Sebagai sumber hukum untuk isi hukum, dalam hal mana kita mengingat pertanyaan : apabilakah isi hukum itu dapat dikatakan tepat sebagaimana mestinya, atau dengan perkataan lain, apakah yang dipakai ukuran untuk menguji hukum agar dapat mengetahui adakah ia ,,hukum yang baik?. 2. Sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum d. Sumber Hukum dalam arti formil Hal-hal ini kita sebut sumber hukum dalam arti formil, karena kita sematamata mengingat cara dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak menanyakan asal-usul isi peraturan-peraturan hukum. Selanjutnya kini kita memakai perkataan sumber hukum dalam arti formil. 1. Sumber hukum dalam arti formil; 2. undang-undang; 3. Kebiasaan;
I Gusti Ngurah Santika, SPd
391
4. Traktat. Dengan berdasarkan pada pembagian sumber hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah kemudian dikatakan bahwa undang-undang termasuk ke dalam sumber hukum yang dikatagorikan dalam arti formil. Hal ini dikarenakan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk dan cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Tentunya berbeda dengan sumber hukum dalam arti materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya : hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas) perkembangan internasional, keadaan geografis (Mertokusumo,1996;70). Dengan demikian, Pancasila merupakan sumber hukum dalam arti materiil, yang menentukan isi hukum bahkan dalam kaitannya dengan hal ini, bahwa Pancasila merupakan cita hukum (rechtsidee), sebagai cita hukum dalam kaitan dengan ini, tentunya Pancasila memiliki dua fungsi, yaitu. (a) fungsi regulatif, artinya cita hukum menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat; (b) fungsi konstitutif, artinya fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cita hukum maka hukum yang dibuat akan kehilangan maknanya sebagai hukum (Attamimi,1992). Dengan demikian, menurut Mahmud MD (2009;61) bahwa peraturan perundang-undangan yang tertinggi (UUD) harus bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UU harus berdasar dan bersumber pada UUD. Berkaitan dengan diberikannya sebuah lembaga kehakiman, untuk menguji sebuah produk politik menurut UUD 1945 merupakan suatu perkembangan yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa undang-undang tersebut dibuat dua lembaga (dalam hal ini DPR dan Presiden) yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Sebenarnya lebih elegan, jika suatu undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif, jika kemudian dalam kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945 seharusnya segera ditinjau pula oleh kedua lembaga yang membuat tersebut (political review or legislative review). Namun, bisa saja memang dalam kenyataaan ada kesengajaan dari para pembentuk undang-undang, untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang jiwanya bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tentunya akan mustahil, untuk suatu lembaga negara yang membuat undang-undang tersebut, kemudian meninjau produknya sendiri. Belajar dari pengalaman masa lalu, kalau hanya mengandalkan legislative review hasilnya tidak begitu menggembirakan karena tidak
I Gusti Ngurah Santika, SPd
392
menampung derasnya aspirasi keadilan yang hidup dan berkembang di tengah aspirasi masyarakat (Yasabari,1984;62). Lagi pula lembaga legislatif sendiri bukanlah sebuah lembaga yang dipandang cocok untuk menguji undang-undang, dikarenakan undangundang sendiri merupakan hukum, karena sudah diundangkan dalam lembaran negara. Sedangkan bilamana yang menguji undang-undang tersebut adalah lembaga politik, tentunya yang menjadi pertimbangan utamanya adalah politis. Lembaga legislatif tidak dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terutama mengeluarkan putusan dalam bentuk pembatalan undang-undang tersebut, melainkan hanya dapat melakukan perubahan terhadap undang-undang melalui hak amandemennya (amandement) ataupun menggantinya dengan undang-undang yang baru, sehingga ketentuan dalam undang-undang tersebut kemudian menjadi tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Yang tentunya berbeda kemudian dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang memang dari awalnya bertugas untuk mengawal supaya konstitusi tersebut dijalankan dengan konsisten (the guardian of constitution) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (the interpreter of constitution). Sehingga, jika dalam kenyataannya ada undang-undang yang kemudian benar-benar bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga ini kemudian dapat menyatakan untuk tidak memberlakukan undang-undang tersebut, dengan cara membatalkannya lewat putusan yang dinyatakan kemudian. Dari sisi hukum dapatlah kemudian dikatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah kelanjutan dari perubahan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi (supremacy of law). Di samping itu, Mahkamah Konstitusi dalam mengawal (guardian), mengontrol (control) dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi yang sering kali hanya mengandalkan kekuatan politik, dapat dikendalikan dan diimbangi dengan prinsip demokrasi itu sendiri dan prinsip konstitusionalisme atau negara hukum (Constitutional democracy or rule of law or rechtsstaat). Untuk lebih jelasnya, terkait dengan adanya perubahan terhadap kekuasaan kehakiman setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, dapat kemudian kita lihat kembali mulai dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 tepatnya dalam Bab IX, bunyi pasal tersebut, yaitu. 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
393
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang (kursif penulis). Terkait dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka Azhary (2006;97) memberikan pengertian kemerdekaan yudisial adalah kemerdekaan dari segala macam bentuk pengaruh dan campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim diwajibkan untuk tetap mempertahankan kemandirian sistem peradilan. Ini artinya bahwa asas imparsial dan bebas merdeka itu tidak boleh digunakan sebagai perisai dalam melindungi anasir-anasir negatif yang mungkin saja bermain ketika peradilan memutus perkara (Asshiddiqie dan Syahrizal,2012;91). Bahkan, dengan adanya doktrin kebebasan kekuasaan peradilan, kemudian Soepomo (2005;67) berpendapat dengan menyatakan bahwa dimana undang-undang memberi peraturan, hakim adalah bebas di dalam menentukan keputusannya. Asas kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa. Yang dimaksudkan dengan kebebasan peradilan atau hakim ialah bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil (Mertokusumo,2006;46). Kemerdekaan dan kebebasan hakim dalam arti luas yaitu bebas dari pengaruh pemerintah maupun kekuatan di luar pemerintah (pendapat umum, pers dan sebagainya) (Manan dan Magnar,1997;91). Hal ini dikarenakan menurut Basah (1985;28) bahwa peradilan merupakan suatu kekuasaan (dalam arti functie), yang berdiri sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya. Dalam hal ini berarti tidak dibenarkan untuk mempengaruhi hakim baik dengan melalui tekanan, paksaan maupun karena kekuasaan yang dimilikinya sehingga hakim merasa tidak bebas dalam memberikan keputusan (Afandi,1981;65). Agar pengadilan benar-benar dapat menjadi benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan (Nasution,2007;6). Sehingga, menurut Supriyanto (2004;10) dengan pendapatnya menyatakan bahwa the Independence of Judiciary is core element of supremacy of law and democracy) yang sangat didambakan, dapat terwujud. Maka, seharusnya dalam hal ini, hakim memutuskan sendiri, memberi intepretasi sendiri atas kewenangannya sendiri dan dia terikat pada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Seorang hakim tidak hanya tergantung kepada siapapun, namun dia juga harus tidak memihak (Hadjon,dkk,2005;289). Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009). Bahkan, para pencari keadilan dapat mengawasi peradilan, karena memiliki hak ingkar, sehingga hakim menjadi lebih objektif dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
394
memeriksa kasus (lihat ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Tidak lain bertujuan agar tugas yang dilakukan badan ini mencerminkan keadilan yang objektif (Azhary,1986;61). Dengan perkataan lain bahwa yang wajib ditegakan oleh hakim itu bukan hanya hukum akan tetapi secara sekaligus juga keadilan (Kuffal,2004;39). Karena keadilan adalah unsur dari hukum (Mertokusumo,2005;9). Mahmud MD (2010;87) menyatakan bahwa kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan kekuatan di luarnya merupakan masalah esensial dalam penegakan hukum. Terkait dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mertokusumo (2006;19) kemudian berpendapat bahwa kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun, campur tangan akan menyebabkan hakim tidak bebas dalam menegakan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan (Najih,2008;8). Hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat hukum (Setiyono,2008;33). Dengan demikian, maka Utama (2007;34) berpendapat dengan tegas bahwa badan peradilan di negara hukum, merupakan sub sistem hukum yang paling kentara sekaligus, menjadi wujud nyata bekerjanya hukum. Hal ini tidak lain dikarenakan menurut Huijbers (2011;87) bahwa prinsip kedaulatan kekuasaan yudikatif sangat mendorong perkembangan negara hukum. Peran Lembaga Peradilan yaitu untuk menjamin penerapan hukum dalam masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan mencapai sasaran (Perwita dan Yani,2011;114). Harahap (2005;59-60), menyatakan bahwa tujuan utama amanat kemerdekaan yang diberikan kepada peradilan, agar para pejabat fungsional yakni para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar menegakan hukum dan keadilan berdasarkan hukum dan kebenaran sesuai dengan hati nurani. Hanya peradilan yang bebas dan merdeka yang dapat menegakan hukum dan keadilan hakiki (to the ultimate truth and justice). Dengan demikian, seperti pernyataan tersebut di atas yang pada dasarnya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, maka Mahkamah Konstitusi tentunya juga merdeka dalam menjalankan tugas. Hal ini tidak lain dikarenakan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, di samping adanya Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat diintervensi oleh kekuatan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
395
apapun, sehingga diharapkan putusan yang diambilnya kemudian adalah berdasarkan kebenaran dan keadilan, yang tentunya selalu menjungjung tinggi konstitusi sebagai pedomannya. Kalau larangan campur tangan dari kekuasaan extra-judissiil ke dalam bidang peradilan itu pada umumnya diakui sebagai salah satu aspek dari peradilan bebas, sebaliknya campur tangan kekuasaan yudikatif ke dalam bidang eksekutif dan legislatif dalam bentuk judicial review belumlah ada pemecahannya yang memuaskan (Mertokusoumo,2011;129). Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, berdampingan dengan Mahkamah Agung, yang juga merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Keduanya tidak memiliki hubungan secara vertical namun memiliki hubungan secara horizontal sebagai lembaga negara. Dan juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 24 bahwa Mahkamah Agung memiliki empat peradilan yang ada dibawahnya, yang pada akhirnya semua keputusan berpuncak kepada Mahkamah Agung. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung serta keempat badan peradilan di bawahnya, keempat peradilan yang dimaksud adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu juga diakui adanya Mahkamah Konstitusi, yang berdiri di luar Mahkamah Agung (supreme court) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sejajar dengan Mahkamah Agung, yang dinyatakan sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimaksudkan oleh UndangUndang Dasar 1945. Keduanya adalah penyelenggara tertinggi dari kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dapat kemudian dikatakan bahwa dengan adanya perubahan UUD 1945, maka selain Mahkamah Agung sebagai puncak pelaksana kekuasaan kehakiman dari lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, juga terdapat Mahkamah Konstitusi yang secara fungsional juga sebagai pelaksanan kekuasaan kehakiman, namun tidak mempunyai hubungan struktural dengan MA (Latif,2009;50). Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan pula dalam UUD 1945, maka dapatlah kemudian dilihat dari ketentuan Pasal 24C UUD 1945, yang mengatur hal-hal berkaitan dengan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Untuk itu marilah kemudian kita simak kembali ketentuan dari Pasal 24C UUD 1945, yaitu sebagai berikut.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
396
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. 5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang (kursif penulis). Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diatur kembali berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu. 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (kursif penulis). Berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
397
Konstitusi memiliki kewenangan untuk menjaga konstitusi, dengan jalan menguji undangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif, dikarenakan memang diperintahkan oleh konstitusi. Dalam kenyataannya Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban lainnya, seperti apa yang telah ditentukan dalam UUD 1945 tentang kewajiban MK untuk memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Presiden menurut UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 merupakan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya, bahkan dinyatakan bahwa putusannya final sejak diucapkan, dan tidak ada upaya hukum lagi untuk melawan putusan tersebut. Pernyataan tersebut kemudian juga dapat diketahui dari Penjelasan 10 UU No. 8 Tahun 2011, yang pada dasarnya telah mengubah bunyi penjelasan pada pasal yang sama dalam UU No. 24 Tahun 2003, bunyi penjelasan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)(kursif penulis). Juga ditentukan kembali dalam ketentuan ayat (2) Pasal 24C UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memutuskan pendapat DPR terkait dugaan pelanggaraan hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Bahkan banyak yang kemudian mengatakan bahwa adanya ketentuan ayat (2) dari Pasal 24 UUD 1945 tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan hanyalah merupakan kewajiban hukum, hal mana dikarenakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidaklah bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksudkan di atas. Karena dalam UUD 1945 sendiri masih diperlukan proses politik, terutama setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, hal mana semuanya memang telah ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Berkenaan dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk selanjutnya dapatlah dikemukakan terlebih dahulu tentang teori berkenaan dengan pengertian hak uji pada umumnya. Dengan tujuan utamanya adalah untuk lebih memahami apa maksudnya. Mengenai istilah atau pengertian hak uji atau totsingrecht (bahasa Belanda) ini, oleh Jimly Asshiddiqie dibedakan antara toetsingsrecht, judicial review, judicial preview, legislative review, executive review, constitutional review. Menurut Asshiddiqie dalam Said (2011;79-80) bahwa hak atau kewenangan menguji atau hak menguji atau hak uji dalam bahasa Belandanya disebut toetsingsrecht itu
I Gusti Ngurah Santika, SPd
398
diberikan kepada hakim, maka namanya adalah judicial review atau review oleh lembaga peradilan. Jika kewenangan menguji diberikan lembaga legislative, maka namanya bukan judicial rivew melainkan legislative review. Jika yang melakukan pengujian itu adalah pemerintah, maka namanya tidak lain adalah executive review, bukan yudicial review. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka menurut pendapat Ranggawidjaja yang kemudian menyatakan ada tiga katagori besar tentang pengujian peraturan perudangundangan, yaitu. 1. Pengujian oleh badan peradilan(yudicial review), 2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political review), dan 3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative review) (Ranggawidjaja,1998;101). Sedangkan, jika pengujian dilakukan kemudian terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and abstract norm) secara a posteriori maka pengujiannya dapat disebut judicial review, tetapi jika pengujian itu bersifat apriori yaitu terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, maka namanya bukan judicial review, melainkan judicial preview. Jika ukuran pengujian itu dilakukan dengan dengan menggunakan Konstitusi sebagai alat pengukur, maka pengujian semacam itu disebut sebagai constitutional review atau pengujian konstitusional, yaitu pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (judicial review on the constitutionality of law) (Asshiddiqie,2010;6). Apabila norma yang diuji itu menggunakan undang-undang sebagai batu ujinya (maksudnya alat pengukur), seperti hak uji yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, maka pengujian itu tidak dapat disebut constitutional review, melainkan judicial review on the legality of regulation. Namun, dalam sejarah perjalanannya semenjak dibentuk, ternyata MK telah menuai berbagai pujian maupun kritikan, terutama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945. Bahkan, dengan berbagai argumen yang mencoba untuk memberikan dukungan ataupun yang memang tidak menyetujui daripada keberadaan lembaga negara ini. Berikut ini, merupakan argumen yang dikemukakan oleh M. Dimyati Hartono (2009;69) tentang ketidaksetujuannya terhadap keberadaan daripada lembaga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
399
Mahkamah Konstitusi tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (constitutional system). Menurut pendapatnya bahwa dengan adanya MK telah menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, khususnya kewenangannya dibidang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, karena bahwa. Undang-Undang adalah Produk Politik yang berdasar keputusan politik, dalam bentuk yuridisnya, adalah sebuah undang-undang. Apakah layak Mahkamah Konstitusi, sebagai sebuah lembaga yang ada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman dan tidak mendapat delegasi kewenangan politik dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat (kursif penulis), mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang yang merupakan produk politik yang dibuat oleh lembagalembaga yang mempunyai delegasi politik dari rakyat (MPR/DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat)? Di sinilah kontradiksi dan problematik dan konseptual yang timbul dari amandemen yang melahirkan Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa bahwa undang-undang yang merupakan hukum adalah produk politik, sebagai sebuah produk politik terdapat kepentingan-kepentingan politik yang mendorong lahirnya suatu undang-undang.Terkait dengan undang-undang sebagai produk politik, maka dapatlah dirujuk kemudian pendapat dari Mahmud MD (2011;5) yang menyatakan bahwa hukum adalah produk politik adalah benar jika di dasarkan pada das sein dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang. Dalam faktanya jika hukum dikonsepkan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristialisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Kemudian masih berkaitan dengan hal tersebut di atas, terutama hubungan politik dan hukum, maka menurut Sri Soematri dalam Halim (2000;18) mengkonstatasikan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel, maka politik sebagai lokomotifnya, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang semestinya dilalui. Oleh karena itu, undangundang dibentuk oleh lembaga legislatif adalah merupakan produk politik, tentunya merupakan hasil daripada pilihan-pilihan politik yang ada pada saat kebijakan itu akan dibuat, sehingga pilihan politik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap produknya (hasilnya), yaitu undang-undang. Dengan demikian hukum bukan gejala yang bebas nilai, tetapi di dalamnya terdapat perkaitan atau hubungan erat sekali dengan politik. Hukum selalu merupakan produk dari proses politik (Latif dan Ali,2010;29). Tanpa adanya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
400
kekuatan politik yang mendorongnya, maka tidak akan pernah ada suatu undang-undang dapat lahir kemudian. Oleh karena itu, kekuatan politik merupakan latar belakang, yang kemudian sangat menentukan dalam pembentukan undang-undang. Di samping itu, pergulatan-pergulatan kepentingan yang mewarnai pada saat perumusan undang-undang, di samping dengan adanya pandangan berbeda tersebut, pada akhirnya kemudian dapat membuat undang-undang tersebut banyak menampung beragam kepentingan berbeda, sehingga pada akhirnya kompromistis sifatnya. Soekanto dkk, (1981;20) menyatakan bahwa terjadi pergulatan-pergulatan kepentingan antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan produk politik, yang kemudian ditetapkan sebagai produk hukum. Dengan adanya pergulatan politik, maka kekuatan politik terbesarlah dapat dipastikan akan selalu memenangkannya, tanpa adanya kekuatan politik mayoritas yang memang mendukungnya, maka kepentingan politik tersebut tidak akan dapat dijadikan sebuah kebijakan dalam bentuk undang-undang. Oleh karenanya, dapatlah kemudian dinyatakan bahwa undang-undang merupakan hasil suatu proses pembentukan yang berbelit (Iver,1988;25). Berkaitan dengan undang-undang yang dalam kenyataannya dibuat oleh parlemen bersama pemerintah, Mahmud MD (2011;10) kemudian berpendapat dengan menyatakan bahwa sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat undang-undang (UU) sebagai produk hukum pada hakekatnya merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik dan menjadi UU. Undang-undang sebenarnya hanya syarat-syarat yang ditetapkan asosiasi politis (Rousseau,1989;40). Dengan demikian, jika dalam kenyataannya sudah ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang, kemudian lembaga ini bertugas untuk mengajukan, membahas sampai dengan menetapkan undang-undang, sesuai dengan apa yang kemudian dipersyaratkan oleh konstitusi, agar produknya itu dapat disebut sebagai undang-undang (formal). Namun, karena banyaknya jumlah kepentingan yang ada dalam badan tersebut, tentunya tidak sedikit aspirasi politik yang dibawa oleh anggotaanggota dalam badan tersebut, selaku pelaku politik agar dapat meloloskan kepentingannya. Tentunya kepentingan-kepentingan dalam badan legislatif, yang dibawa oleh anggotaanggota badan tersebut, sangatlah berpengaruh terhadap produk hukum yang kemudian akan dilahirkannya. Bahkan, anggota-anggota dalam badan tersebut ternyata bukanlah satusatunya sebagai penyebab utama yang kemudian membentuk karakter hukum, karena dapat saja pengaruh tersebut datang dari rezim yang sedang berkuasa ketika itu. Pernyataan tersebut dikemukakan dikarenakan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud MD dalam Syaukani dan Thohari (2010;5-6) bahwa suatu proses dan konfigurasi politik
I Gusti Ngurah Santika, SPd
401
rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkan. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik, sedangkan untuk di negara yang konfigurasinya politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter ortodoks dan konservatif atau elitis. Hal ini dapatlah diambil berdasarkan kesimpulan dari pendapat Fuadi (2011;8) yang menyatakan bahwa ketika suatu undang-undang dibuat oleh parlemen, atau ketika suatu aturan hukum diterapkan baik oleh parlemen ataupun oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka hukum yang dibuat tersebut tidak memperhatikan adanya aneka ragam persepsi masyarakat. Maka, produk hukum yang dilahirkan kemudian adalah produk hukum yang sifatnya elitis, konservatif dan ortodok, karena mementingkan penguasa. Dengan demikian, dapat selanjutnya dikatakan bahwa kegiatan lembaga legislatif merupakan pekerjaan, yang mengolah berbagai kepentingan politik agar dapat disatukan, kemudian menjelma menjadi sebuah bentuk aturan dengan sifat mengatur, mengikat dan bahkan memaksa rakyat agar dipatuhi, yakni dalam bentuk undang-undang. Lebih lanjut terkait dengan hal tersebut di atas, maka Mahmud MD (2010;65) menyatakan bahwa dalam kenyataannya, kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) memang lebih banyak memuat keputusan-keputusan politik ketimbang menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya sehingga lembaga legislatif lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum. Sehingga untuk itu, diperlukan tranparansi dalam proses legislasi, berkaitan dengan hal tersebut Munti (2008;12) menggambarkan proses legislasi yang harus disadari sebagai hal yang kompleks karena tidak transparan sehingga hanya dimengerti dan diakses oleh sebagian kecil masyarakat. Bahkan, karena ketidak transparanan dalam pembentukan undang-undang, sehingga di dalam suatu undang-undang ternyata terdapat motif-motif tertentu, hal mana motif tersebut merupakan maksud dari pembentuk undang-undang. Bahkan, Atkinson dalam Martaniah (1984;13) menganggap motif sebagai suatu diposisi laten yang berusaha dengan kuat untuk menuju ke tujuan tertentu; tujuan ini dapat berupa prestasi, afiliasi, ataupun kekuasaan. Kesemua hal di atas menandakan bahwa kebijakankebijakan publik terlahir melalui proses-proses politik yang tidak sederhana (Rohman,2009;94). Keputusan politik di dalam demokrasi pada akhirnya menjadi suatu pilihan dari alternatif kebijakan yang ada (Maab dan Fauzan,2012;6). Untuk itu diperlukan suatu pedoman yang wajib diikuti oleh setiap pembentuk hukum di negara Republik Indonesia (Wijaya,2008;400). Apalagi sejak semula, seperti halnya di Indonesia ini, prosedur pembuatannya haruslah demokratis (Rahardjo,1980;22). Bahkan dapat dikatakan kemudian bahwa karakteristik hukum (undang-undang) yang baik adalah diterima oleh masyarakat, tidak lain karena hukum itu sendiri bersifat terbuka, memberitahu terlebih
I Gusti Ngurah Santika, SPd
402
dahulu, tujuannya jelas, mengatasi goncangan. Bahkan, dapat saja UU yang dibuat ternyata bertentangan dengan moral dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral, perundang-undangan yang immoral harus diganti (Setiadi,2010;143). Karenanya, merupakan ukuran tambahan bagi Mahkamah Konsitusi untuk menilai lebih lanjut terkait dengan suatu produk undangundang yang bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Kemudian sesuai dengan badan yang membuat (menetapkan) undang-undang mempunyai derajat di bawah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusiderajat tinggi (supreme constitution). Ini berarti bahwa isi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (Busroh,1994;122). Maka berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan karena Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pengujian undang-undang berarti memakai konstitusi sebagai alat pengukurnya (batu uji), sehingga dapat disebut dengan constitutional review. Dengan konsekuensi itu juga MK berfungsi sebagai penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution) (Mahkamah Konstitusi,2010;1-2). Berkaitan pengujian norma hukum, pada kesempatan ini Soemantri (1986;5) menyatakan pendapatnya, dengan mengadakan pembedaan adanya dua macam hak menguji, yaitu sebagai berikut: a. Hak menguji formal (formale toetsingsrecht), dan b. Hak menguji Material (materiele toetsingsrecht). Terjadinya perubahan dari kedua macam hak uji tersebut di atas, dikarenakan adanya perkembangan atau perubahan pengaturan pokok yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (Soehino,2007;1). Dapat dikatakan bahwa Hak menguji formal terhadap undangundang adalah berkenan prosedur dalam pembuatan undang-undang yang bersangkutan apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasarnya. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku (Mertokusumo,1996;70). Dengan kata lain, menurut Sanusi (1984;71) bahwa Uudang-undang dalam arti ini ditinjau dari sudut pembentukannya. Dengan pendapat sama, Huijbers (2010;42) kemudian menyatakan bahwa terkait dengan keabsahan hukum jika ditinjau secara formal adalah lazim diterima bahwa hukum adalah legal, bilamana undang-undang dan peraturan yang ditentukan oleh suatu instansi yang berwenang, yakni pemerintah yang sah, dan ditentukan menurut criteria yang berlaku. Tidak lain, karena kita semata-mata mengingat cara dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak menanyakan asal-usul isi peraturan hukum (Apeldoorn,2011). Dengan demkian, ini berkaitan dengan dengan bentuk atau cara yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
403
menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku (Ridwan HR,2011;61). Bentuk hukum tertulis macam ini dinamakan undang-undang dalam arti formal, yakni hukum tertulis produk suatu badan legislatif yang melibatkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Kusumaatmadja dan Sidharta,999;60). Menurut Kansil dan Christine (2002;157) bahwa hak uji formil, yaitu hak untuk menyelediki apakah undang-undang tersebut pada saat dibentuknya adalah sesuai dengan acara yang sah. Mahkamah Konstitusi merupakan organ penjaga konstitusi, misalnya dapat diberikan wewenang untuk hanya menyelidiki apakah norma yang harus diterapkan kepada suatu kasus konkret itu benar-benar telah dibuat oleh organ legislatif; atau apakah norma itu telah dibuat oleh suatu organ legislatif atau eksekutif yang kompeten untuk menerbitkan norma-norma umum (Kelsen,2011;378). Dapatlah dikatakan kemudian bahwa berkaitan dengan pengujian undang-undang secara formal oleh MK adalah untuk menyediki UU yang dikaitkan dengan cara terjadinya dan lembaga (Mahmud MD dan Marbun,2000;25). Lembaga yang dimaksud tersebut adalah lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan tersebut. Dengan demikian, pendapat di atas tersebut adalah sesuai dengan ketentun Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 2011, yang berkaitan dengan adanya asas kelembagaan dan pejabat pembentuk yang tepat. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundangundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang (kursif penulis). Berkaitan dengan pengertian kata dibatalkan dan batal demi hukum, Mahmud MD (2010;235) menyatakan bahwa dibatalkan berarti ketidakabsahannya berlaku sejak tanggal ada pembatalan; sedangkan batal demi hukum berarti ketidakabsahannya mulai berlaku sejak peraturan itu ditetapkan (yang berarti membatalkan pula akibat-akibat hukum yang timbul sebelum ada pembatalan). Dapat dikatakan bahwa menguji secara material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya (Soemantri,1986;8). Dan jika terbukti maka bagian itu saja yang akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Isra,2010;9). Kualitas materi UU berkaitan dengan apakah pasal-pasal dalam sebuah UU sudah mencerminkan aspirasi masyarakat dan dapat menjadi titik masuk bagi upaya perbaikan kehidupan masyarakat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
404
dalam segala aspeknya (Hasan,2007;58). pengujian materiil dapat dilakukan, apabila ada peraturan yang isinya benar-benar bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Soemantri,1993;55). Dengan adanya ketentuan ini maka peraturan hukum yang dibuat harus sesuai dengan jenis, hierarki dan muatan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 hurf c UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (kursif penulis). Pada intinya dasar dari adanya pembedaan antara pengujian secara formal dan materiil adalah akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya membatalkan undang-undang tersebut. Jika pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan secara formal, berakibat pula bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan membatalkan daripada keseluruhan undang-undang yang dimintakan pengujian. Hal ini dapat dilihat kemudian dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (kursif penulis).Tentunya berbeda dengan pengujian undang-undang secara material, yang hanya mengakibatkan beberapa pasal atau bagian tertentu saja dari undang-undang tersebut kemudian dinyatakan batal/tidak mengikat, dalam arti tidak terhadap pasal/bagian lain dari undang-undang yang sebelumnya tidak dimintakan pengujian. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil dapat pula dilihat kemudian dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (kursif penulis) . Dapat dikatakan, apabila suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dasar yang dilihat dari segi isinya, maka isi atau bagian tertentu yang dimintakan pengujian dalam undang-undang tersebut, harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat. Yang berarti diuji hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian, ayat, dan pasal tertentu saja yang kemudian
I Gusti Ngurah Santika, SPd
405
dianggap bertentangan dengan konstitusi, sehingga dapat dinyatakan batal, di samping tentunya bagian, ayat, dan pasal yang diujikan sebelumnya tidaklah memiliki kekuatan untuk mengikat umum. Bahkan putusan MK ini merupakan putusan final menurut UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan satu pasal bertentangan dengan UUD 1945, tetapi dengan membuang kata yang merupakan bagian kalimat dalam pasal tersebut makna pasal tersebut dapat berubah sama sekali dan dipandang dengan demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Siahaan, 2010;21). Dapatlah kemudian dikatakan bahwa dengan kehadiran MK ini, tentunya akan berbeda dengan dulunya, hal mana merupakan pandangan klasik Montesquieu yang pada dasarnya menyatakan bahwa hakim hanyalah corong dari undang-undang yang tidak dapat mengubah atau menambah undang-undang (Mertokusumo dan Pitlo,1993;6). Konsep kuno tersebut menempatkan hakim hanya sekedar terompet undang-undang yang bersumber dari kalimat yang pernah dikumandangkan oleh Baron de Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755) empat abad silam : the jugde as la bouche de la looi, as the mouthpiece of the law(Ali,2012;477488). Namun untuk sekarang, tampaknya konsep tersebut di atas, tidaklah mungkin lagi untuk diterapkan, dikarenakan telah ditentukan bahwa hakim konstitusi dalam kenyataannya dapat membatalkan undang-undang atau beberapa bagian daripada undangundang, jika dipandang bertentangan dengan undang-undang dasar. Berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka dalam UU No. 24 Tahun 2003 telah diatur pula, berkaitan dengan siapa saja yan kemudian dapat menjadi pemohon untuk mengajukan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi agar nantinya dapat dibatalkan. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara. Selanjutnya berkaitan dengan pengujian undang-undang, apa saja yang perlu untuk diuraikan oleh pemohon, agar Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohon pemohon berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
406
Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya terkait dengan kerugian yang timbul akibat berlakunya undang-undang tersebut. Dalam permohonan tersebut, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tentunya diperlukan kejelasan tentang rambu-rambunya, agar apa yang kemudian menjadi kewenangannya tidak melampui batas daripada UUD 1945, yang sejatinya telah memberikan kewenangan kepadanya. Dalam ketentuan Pasal 45A UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan (kursif penulis). Pasal tersebut, merupakan ketentuan mengenai pembatasan dalam pengaturan di bidang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Mirip sekali dengan ketentuan tersebut, ternyata dalam hukum perdata terdapat ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) Rbg, yang menyatakan Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuh putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Mertokusumo,2006;12). Adanya ketentuan tentang larangan bagi MK, agar nantinya tidak membuat putusan yang pada dasarnya tidaklah diminta ataupun melebihi permohonan pemohon, terkait dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang besifat ultra petita (tidak diminta, atau lebih daripada yang diminta), jika itu dilakukan tentunya akan mengarah intervensi ke dalam bidang legislasi. Pada umumnya pembatasan tugas yang demikian, dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah, adalah positive legislator (pembuat norma) sedangkan MK adalah negative legislature (penghapus atau pembatal norma). Dengan begitu, hampir tidak dapat dielakan adanya suatu antagonisme di antara dua lembaga pembuat undang-undang, yakni pembuat undang-undang dalam arti positif dan pembuat undang-undang dalam arti negatif (Kelsen,2011;379). Ini penting ditekankan karena secara historis dan filosofis UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak membolehkan MK mengintervensi ranah legislatif dengan ikut menjadi positive legislator (memberlakukan norma). Yang boleh dilakukan oleh MK hanyalah menjadi negative legislator (membatalkan norma) atau membiarkan norma yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
407
diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original inten UUD 1945 sebagai tolok ukurnya (Mahmud MD,2009;280). Selain adanya pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, juga ditentukan pembatasan lainnya dalam ketentuan Pasal 50A UU No. 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa : Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum(kursif penulis). Jika, kemudian Mahkamah Konstitusi dalam kenyataannya menggunakan undang-undang lainnya sebagai dasar pertimbangan hukum, untuk membatalkan suatu undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi dapat dipastikan telah melanggar ketentuan Pasal 24C UUD 1945, yang pada dasarnya telah menggariskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang dengan menggunakan UUD 1945 sebagai batu ujinya (constitutional review), bukannya undangundang yang kedudukannya berada pada hierarki yang sama dengan diujinya, karena tugas tersebut pada dasarnya merupakan kewenangan lembaga legislatif untuk mengaturnya (legislative review, political riview). Selain itu, letak kewenangan untuk mengatur pertentangan antara undang-undang yang satu dengan lainnya, tentunya bukanlah kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi, melainkan dalam hal ini adalah tugas daripada lembaga legislatif, melalui kewenangan legislative review yang dimilikinya. Dengan demikian, tidak diperbolehkannya Mahkamah Konstitusi yang mendasarkan putusannya berdasarkan adanya pertentangan antara undang-undang yang diuji dengan undang-undang lainnya, adalah benar-benar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sekaligus sebenarnya juga menghindarkan Mahkamah Konstitusi, untuk mencampuri urusan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif, karena kewenangan tersebut berada pada ranah legislatif, bukan lembaga yudikatif. Ini merupakan suatu konsekuensi dengan dianutnya sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) di antara lembaga-lembaga negara, dengan demikian tidak diperkenankan untuk mencampuri urusan yang berada di luar kompetensi masing-masing lembaga negara, yang sebenarnya telah digariskan oleh UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 terdapat pula larangan lain terhadap Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusannya yang tidak boleh memuat. a. . b. Perintah kepada pembuat undang-undang; dan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
408
c. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (kursif penulis). Dalam melakukan tugasnya berupa pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang mengatur; atau dengan kata lain, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, tidak boleh disertai dengan pengaturan misalnya cara dan lembaga mana yang kemudian harus mengatur kembali, isi undang-undang yang sebelumnya dibatalkan tersebut. Tidak lain dasar dari adanya pengaturan seperti ini ialah, dikarenakan UUD 1945 pada dasarnya telah menggariskan hubungan, antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep yang dianut oleh UUD 1945 untuk sekarang ini, tidak lagi menempatkan satu lembaga negara sebagai lembaga yang tertinggi kedudukannya, dengan menempatkan lembaga-lembaga negara lainnya berada di bawah kedudukannya. Kesimpulannya jika Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan undangundang dengan disertai perintah untuk pengaturan kepada lembaga negara, yang bertugas untuk mengaturnya atau melakukan tindakan untuk memperbaiki sendiri undang-undang yang bersangkutan, maka Mahkamah Konstitusi telah menyimpangi konsep hubungan kelembagaan negara, padahal telah ditentukan berkaitan dengan kedudukan antara lembaga negara satu dengan lainnya adalah sejajar, walaupun adanya pengaturan untuk saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dilarang memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Jika Mahkamah Konstitusi memuat suatu putusan, yang di dalamnya terdapat rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tentunya Mahkamah Konstitusi bukan lagi sebagai lembaga yudisial melainkan sebagai lembaga legislatif. Karena dalam pembagian ataupun pemisahan kekuasaan (distribution or separation of power), sudah ditentukan kompetensi masing-masing lembaga negara, khususnya berkaitan dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing, seperti halnya dalam teori Montesquieu yang kemudian memisahkan ketiga lembaga negara, yaitu legislatif sebagai lembaga pembentuk norma, eksekutif sebagai pelaksana norma, dan yudikatif sebagai mengadili atas pelanggaran norma (bahkan untuk sekarang dapat membatalkan norma).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
409
Selain, adanya larangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan, dan kenegarawanan hakim konstitusi telah ditentukan pula dalam ketentuan Pasal 27B hurub b angka 3 UU No, 8 Tahun 2011 yang pada dasarnya menyatakan bahwa hakim konstitusi dilarang mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan. Kalau ditafsirkan secara berkebalikan (contrario) terhadap ketentuan tersebut, maka hakim konstitusi tentunya dapat mengeluarkan pendapatnya di luar persidangan, asalkan terkait dengan kasus tersebut sudah diputuskan terlebih dahulu. Misalnya pendapat-pendapat tersebut disampaikan pada seminar-seminar, kegiatan ilmiah, maupun dalam kegiatan lainnya. Berkaitan dengan rambu-rambu Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan kewenangannya dalam bidang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar tidak melampaui batas atau tentunya tidak masuk dalam ranah kekuasaan lain dan menjadi politis, maka ada sepuluh dalam rumusan negatif (pelarangan) menurut Mahmud MD (2009;281-284) yang perlu diperhatikan, yaitu. 1. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas UU, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur; pembatalan undang-undang tidak boleh disertai pengaturan, misalnya dengan putusan pembatalan yang disertai isi, cara, dan lembaga yang harus mengatur kembali isi UU yang dibatalkan tersebut. Ini harus ditekankan karena bidang pengaturan adalah ranah legislatif. Jadi MK hanya boleh mengatakan suatu UU atau isinya konstitusional atau inkonstitusional yang disertai pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas UU, MK tidak boleh membuat ultra petita (putusan yang tidak diminta oleh pemohon) sebab dengan memuat ultra petita berarti MK mengintervensi ranah legislatif. Meski begitu ada juga yang berpendapat bahwa ultra petita boleh dilakukan oleh MK jika isi undangundang yang dimintakan judicial review berkaitan langsung dengan pasal-pasal lain yang tak dapat dipisahkan atau menjadi jantung masalah tersebut. Pemikiran seperti itu wajar, tetapi bagi penulis sendiri kalau sebuah pasal undang-undang yang dimintakan uji materi ada kaitan dengan pasal-pasal lain yang tidak diminta untuk dibatalkan maka pembatalan tak bisa dilakukan atas pasal yang tidak diminta karena kalau itu dilakukan berarti merambah ke ranah legislatif. Bahwa pasal yang dibatalkan itu berkaitan dengan pasal lain, biarkanlah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
410
pembentulan/revisinya dilakukan oleh lembaga legislatif sendiri melalui legislative review. Toh, jika ada pasal di dalam undang-undang menjadi tidak berlaku karena ada pasal lain yang dibatalkan oleh MK dengan sendirinya pasal tersebut tak dapat dilaksanakan sehingga dengan sendirinya pula lembaga legislatif dituntut untuk melakukan legislative review. 3. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang lainnya, sebab tugas MK itu menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD, bukan undang-undang terhadap undang-undang yang lainnya. Tumpang tindih antar berbagai undang-undang menjadi kewajiban lembaga legislatif untuk menyelesaikannya melalui legislative review. 4. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri. Apa yang diserahkan secara terbuka oleh UUD untuk diatur oleh undang-undang berdasar pilihan politik lembaga legislatif tidak bisa dibatalkan oleh MK kecuali jelas-jelas melanggar UUD 1945. Di dalam UUD 1945 sendiri banyak masalah yang diserahkan untuk diatur berdasar kebutuhan dan pilihan politik lembaga legislatif yang tentunya tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain, termasuk oleh MK. 5. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi, sebab teori itu amat banyak dan bermacammacam sehingga pilihan atas satu teori bisa bertentangan dengan pilihan atas teori lain yang sama jaraknya dengan UUD. Begitu juga, dengan putusan MK tidak boleh didasarkan pada apa yang berlaku di negara-negara lain, semaju apa pun negara tersebut; sebab di negara-negara lain pun ketentuan konstitusinya dapat berbeda-beda. Oleh sebab itu, yang harus menjadi dasar adalah isi UUD 1945 dan semua original intent-nya. 6. Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh melanggar asas nemo judex in causa sua, yakni memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri. 7. Para hakim MK tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada publik atas kasus konkret yang sedang diperiksa MK, termasuk dalam seminar-seminar
I Gusti Ngurah Santika, SPd
411
dan pada pidato-pidato resmi. Ini penting agar dalam membuat putusan nantinya hakim MK tidak tersandera oleh pernyataan sendiri dan masyarakat pun tidak terpolarisasi oleh dugaan-dugaan tentang putusan yang akan dikeluarkan oleh MK. 8. Para hakim MK tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapa pun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke MK. Biarlah yang mengambil inisiatif untuk itu justiabelen sendiri. 9. Para hakim tidak boleh terlibat secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam silang sengketa politik antar lembaga-lembaga politik, sebab tindakan menawarkan diri itu sifatnya politik, bukan legalistik. Mungkin menjadi penengah politik itu bertujuan baik. Ada banyak lembaga lain yang lebih proporsional untuk menengahi perseturuan politik melalui kerja-kerja politik. Biarlah dinamika politik bekerja, bergulat, dan selesai di ranahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan koridor-koridor etis yang tersedia. 10. MK tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik atau buruknya UUD, atau apakah UUD yang sedang berlaku itu perlu di diubah atau dipertahankan. MK hanya wajib melaksanakan atau mengawal UUD yang sudah ada dan berlaku sedangkan urusan mempertahankan atau mengubah adalah urusan lembaga lain yang berwenang (kursif penulis). Dalam UU No. 8 Tahun 2011 telah ditentukan pengaturan tentang Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, yang ditegakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Untuk menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, maka dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada: Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan norma dan peraturan perundang-undangan. Untuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
412
menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan, dan kenegarawanan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Selain itu, ditentukan pula dalam UUD 1945 bahwa MK memiliki tugas untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Artinya hanya lembaga-lembaga yang ditetapkan dalam UUD 1945, serta telah ditentukan pengaturannya tentang apa saja yang menjadi kewenangannya. Dan jika kemudian ada lembaga negara yang telah ditentukan kewenangan oleh UUD 1945, merasa bahwa kewenangannya tersebut dalam kenyataannya telah dilanggar oleh lembaga negara lainnya, maka terkait dengan masalah ini dapat saja diajukan ke MK untuk kemudian diputus. Hal mana adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (kursif penulis). Ketentuan Ayat (2) dalam pasal yang juga sama menyatakan bahwa : Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi(Pasal 63 UU No. 8 Tahun 2011). Namun, dalam UU No. 24 Tahun 2003 juga dinyatakan pembatasan terhadap lembaga negara, yang tidak bisa berpekara dalam persengketaan kewenangan lembaga-lembaga negara. Dalam ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden (Pasal 67 UU No. 24 Tahun 2003). Di sini, pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa (Nurtjahjo dan Fuad,2010;46). MK juga berwenang untuk membubarkan partai politik, jika ternyata ada suatu partai politik yang perbuatannya nyata-nyata dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI. Misalnya saja, ada sebuah partai yang aliran ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan NKRI, maka bisa saja dibubarkan oleh MK. Bahkan dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
413
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tepatnya dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam UU No. 24 Tahun 2003 ditetapkan bahwa hanya pemerintahlah yang menjadi pemohon, atau dengan kata lain, yang dapat mengajukan pembubaran partai politik dengan alasan seperti tersebut di atas. Dengan demikian, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 hanya memberikan kepada pemerintah legal standing, untuk mengajukan permohonan, agar partai politik tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, mengapa tidak kepada yang lain untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon agar dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembubaran partai politik, seperti misalnya partai politik sendiri? Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Safa;at (2011;275) apabila hak pengajuan pembubaran diberikan kepada pihak lain, termasuk partai politik, berarti partai politik dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Hal itu harus dihindarkan karena dalam demokrasi seharusnya sesama partai politik bersaing secara sehat. Oleh karena itu, partai politik tidak boleh diberikan kedudukan sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Lebih lanjut menurutnya, mengingat juga pemerintah terbentuk dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum, maka dapat menjegal saingannya dengan memanfaatkan label pemerintah dalam membubarkan partai politik lain. Oleh karena itu, wewenang pembubaran partai politik tidak dapat diserahkan kepada pemerintah tetapi harus melalui peradilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Pemerintah hanya bertindak sebagai penuntut dengan cara mengajukan permohonan. Dengan demikian, sebenarnya walaupun partai politik diberikan kedudukan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik, penulis rasa sah-sah saja. Pemikiran tersebut didasari, oleh dikarenakan jika kita kemudian berpikir secara kebalikannya (a contrario) bahwa hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik. Maka segi negatif yang kemudian didapat, misalnya pemerintah yang juga kita ketahui dibentuk melalui partai politik, yang sebelumnya memenangkan pemilihan umum, ternyata dalam perjalanannya partai pendukung pemerintah tersebut, telah melakukan tindakan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tentunya dalam hal ini partai pemerintah tersebut jelas-jelas ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik politik yang bersangkutan jelas-jelas bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun karena pemerintah sebagai pemohon satu-satunya yang diberikan oleh Pasal 68 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003
I Gusti Ngurah Santika, SPd
414
ternyata tidak mengambil keputusan, untuk mengajukan partai politiknya agar dibubarkan dengan mangajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Tentunya dalam hal ini, tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah dengan mengajukan partai politiknya ke Mahkamah Konstitusi untuk dibubarkan, walaupun partai politiknya sudah pastinya melakukan larangan-larangan yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang, yang sebenarnya nyata-nyata kegiatan partai tersebut bertentangan dengan konstitusi. Perhitungan Presiden adalah jika partai politik pendukungnya bubar, maka Presiden akan mengalami kesulitan untuk meraih dukungan di DPR, sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan, kita tahu bahwa peradilan adalah bersifat pasif, terkait dengan kewenangan untuk mengadili kasus, sebelum adanya yang mengajukannya ke persidangan. Dilain pihak, menurut penulis bisa saja partai politik diberikan kedudukan hukum sebagai pemohon, dikarenakan tentunya sesama partai politik akan lebih tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ini merupakan suatu keuntungan tersendiri. Lagipula siapapun yang mengajukan permohonan terkait dengan pembubaran partai politik misalnya, tentu masih perlu dibuktikan secara hukum dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, apakah benar partai politik tersebut memang melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa takut terkait dengan siapa yang diberikan legal standing untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi. Sepanjang terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya kegiatan partai politik, yang melakukan tindakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian bukti-bukti tersebut akan diuji kembali dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. Tugas lain Mahkamah Konstitusi adalah berhubungan dengan pemutusan hasil pemilihan umum yang menjadi sengketa, hal mana tugas tersebut sebenarnya merupakan proses hukum dalam mengawal demokrasi. Agar dapat terpilih para pemimpin yang betulbetul demokratis, karena jika suatu saat terjadi kecurangan dalam penghitungan suara yang menyebabkan kerugian terhadap salah satu kontestan, maka MK berwenang untuk memutuskannya. Untuk itu, pertama kalinya kita akan melihat siapa saja yang ditentukan memiliki kedudukan hukum, dalam mengajukan permohonan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam UU No. 24 Tahun 2003 dalam Pasal 74 ayat (1) dinyatakan yang dapat menjadi pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia; calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian lebih lanjut, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
415
Umum yang mempengaruhi: terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Selanjutnya, dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Selain empat wewenang MK tersebut di atas, ternyata masih ada satu kewajiban lagi bagi MK, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaraan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 (Pasal 24C ayat (2), jo. Pasal 7B). Berkaitan dengan hukum acaranya menurut UU No. 24 Tahun 2003 yang selanjutnya dapat menjadi pemohon adalah DPR, kemudian selanjutnya pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan: Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, juga dipersyaratkan agar permohonan DPR terkait dengan dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disertai keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar. Mahkamah konstitusi beranggotakan sembilan orang, yang tiga orang diajukan oleh DPR, tiga orang lagi oleh MA dan terakhir tiga orang oleh Presiden, kemudian sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang administrasi tertinggi, maka Presidenlah yang menetapkannya sebagai hakim konstitusi lewat keputusan Presiden sebagai bentuk hukumnya (Pasal 24C ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011). Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dari UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
416
anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Konfigurasi sumber rekruitmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara tersebut di dalam tubuh MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem checks and balances antar cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) (Asshiddiqie,2009;307). Kemudian terkait dengan susunan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan, bahwa susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil ketua MK dipilih dari dan oleh anggota MK sendiri (Pasal 24C ayat (4) UUD 1945), Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud di atas dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara lainnya (Pasal 24C ayat (5) UUD 1945), Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi: pejabat negara lainnya; anggota partai politik; pengusaha; advokat; atau pegawai negeri. Penulis rasa dengan adanya larangan merangkap jabatan untuk hakim konstitusi merupakan suatu cara, untuk tetap mempertahankan integritas dan kepribadian hakim sehingga kepribadian yang tidak tercela, adil dan kenegarawanannya dapat dijamin. Pernyataan bahwa yang menjadi hakim MK adalah seorang negarawan merupakan suatu penegasan prinsip bahwa hakim konstitusi merupakan seorang guru bangsa. Mengutip pendapat Marno dan Idris (2009;16) bahwa guru bangsa adalah orang yang dengan keluasan pengetahuan, keteguhan komitmen, kebesaran jiwa dan pengaruh, serta keteladanannya dapat mencerahkan bangsa dari kegelapan.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
417
BAB IV NEGARA HUKUM
A. NEGARA DAN HUKUM Fadjar (2005;1) menyatakan bahwa salah satu tipe negara modern yang banyak dibicarakan ialah negara hukum. Lebih-lebih, mengingat, para pendiri republik ini sepakat bahwa Indonesia ialah negara yang bardasarkan atas hukum (Rechstaat), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (machstaat). Dengan demikian, memang sejak awal berdirinya Indonesia sebagai suatu negara, telah menetapkan untuk berdiri di atas prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Kemudian prinsip ini dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Prinsip ini otomatis juga berlaku dalam segala gerak dan tindakan pelaksanaan negara mulai dari pusat sampai daerah di seluruh Indonesia (Tarmidji,1992;27). Sebelum membahas negara hukum, maka konsep negara dan hukum merupakan dua hal yang dalam kenyataannya tidaklah mungkin dapat dipisahkan, namun kedua konsep tersebut memiliki makna berbeda antara satu dengan lainnya. Dua konsep sebagaimana dimaksudkan tadi adalah berkaitan dengan negara dan hukum, apabila digabungkan kemudian akan membentuk sebuah konsep yang bermakna luar biasa. Negara adalah salah satu konsep daripada bentuk kelompok, tetapi memiliki jumlah anggota sangat banyak, di samping jangkauan wilayah yang sangat luas. Sebenarnya ada berbagai bentuk motivasi yang mendorong manusia untuk kemudian hidup berkelompok. Setiap orang menjadi anggota kelompok tersebut tentunya memiliki motivasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu motivasi paling mendasar adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Abraham Maslow (dalam Maksudi,2012;42) dengan teorinya dinamakan a theory of human motivation yang juga sering disebut sebagai teori kebutuhan disusun secara hieraki atau tingkat-tingkat kebutuhan manusia menjadi lima. Yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis, diikuti dengan kebutuhan-kebutuhan lain seperti rasa aman, penerimaan, harga diri. Aktualisasi diri, penghargaan atau penghormatan, rasa memiliki, dan rasa cinta atau sayang, perasaan aman, dan tentram merupakan kebutuhan fisologis mendasar (Uno,2011;6). Kebutuhan-kebutuhan (needs) tersebut hanya mungkin dapat terpenuhi jika manusia kemudian secara sadar membentuk sebuah kelompok, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kelompok sebagaimana dimaksud di atas
I Gusti Ngurah Santika, SPd
418
dapat dimulai dari jumlah anggotanya paling kecil, yaitu keluarga, sampai dengan kelompok yang bentuknya paling kompleks dan modern, seperti dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan bentuk kelompok sosial yakni keluarga, maka Abdussalam (2007;76) berpendapat bahwa dari berbagai bentuk kelompok sosial, keluarga dipandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, atau keluarga sebagai kelompok utama. Kehidupan berkelompok sebagaimana dimaksud di atas, tidak terlepas dari sifat manusia, disatu pihak memiliki sifat individual, sedangkan dilain pihak juga merupakan makhluk sosial. Dua sifat manusia tersebut (individu dan sosial) memiliki perbedaan-perbedaan, namun selalu dimiliki setiap manusia. Asal kata individu berarti tidak dapat dibagi-bagi. Makhluk individual berarti makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi (in devidere) (Gerungan,2002;22). Dengan demikian, sebagai makhluk individu manusia cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri. Bahkan, secara individu, manusia ingin sekali hidup sebebas-bebasnya tanpa adanya pembatasan dari orang lain. Sehingga kebebasan merupakan akar utama daripada kehidupan individu dan keterikatan merupakan lawannya, karena bersifat membatasi. Namun, jika dilihat dari sudut sosial, manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup menyendiri, dia membutuhkan kehadiran orang lain untuk mambantunya agar dapat memenuhi kebutuhannya. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon, political being, social being, social wezen, makhluk yang senantiasa ingin hidup berkelompok (makhluk sosial) (Sumantri,2003). Pendapat yang senada mengatakan bahwa manusia adalah homo politicus (Kumorotomo,2005;21). Hal tersebut dinyatakan tidak lain dikarenakan, menurut Kaelan (2002;162) bahwa manusia sebagai mahkluk individu maupun mahkluk sosial merupakan sifat-sifat kodrat manusia. Ini berarti bahwa manusia hanya dapat mempertahankan eksistensinya jika dapat hidup berdampingan dengan yang lainnya. Akan tetapi hidup berkelompok dengan yang lainnya memiliki resiko: anda tidak dapat hidup sesuka anda (Dahl,2001;74). Untuk itu, maka mau tidak mau jika kita hidup berdampingan dengan orang lain, memerlukan kesadaran untuk berusaha mengurangi kebebasannya, yang kemudian pada gilirannya bertujuan, agar dapat mempertahankannya ketertiban dalam masyarakat yang baru terbentuk, untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan daripada dibentuknya masyarakat tersebut. Karena pada dasar manusia hidup berdampingan dengan yang lainnya, pastinya sewaktu-waktu bisa saja menimbulkan pergesekan ataupun konflik dikemudian hari. Hal tersebut terjadi diakibatkan oleh adanya berbagai perbedaan kepentingan antara satu individu dengan individu lainnya. Maka, untuk mengatasi konflik tersebut agar tidak terjadi disintegrasi dalam kelompok masyarakat, tentunya diperlukan aturan/hukum bertugas untuk mengatur berbagai perbedaan kepentingan tersebut agar dapat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
419
berjalan beriringan. Menurut Soekanto (2009;242) bahwa apabila keadaan demikian dibiarkan, maka akan timbul kekacauan, karena terjadi benturan dan bahkan bentrokan kepentingan-kepentingan. Yang kemudian mendasari pemikiran tentang adanya hukum, antara lain, adalah perlunya aturan main dalam hidup bermasyarakat sehingga tidak terjadi benturan antar kepentingan sesama anggota masyarakat itu. Dan dengan adanya aturan main yang mengikat semua anggota masyarakat itu, diharapkan kehidupan masyarakat menjadi tertib. Dasar pemikiran seperti itu digambarkan di dalam adagium ubi societas ibi ius, yang berarti dimana ada masyarakat di sana ada hukum(Mahmud MD,200;272). Hukum adalah rangkain peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggotaanggota masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat (Prodjodikoro,2008;15). Oleh karena itu, perlu adanya sebuah organ yang kemudian dapat menjamin bahwa aturan hukum tersebut akan dilaksanakan, demi tercapai tujuan yang memang dicita-citakan dalam membentuk masyarakat. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka dipandang perlu untuk kemudian membentuk sebuah masyarakat yang diorganisir secara politik, dengan tujuan agar mampu mempertahankan eksistensi, maka tentunya harus memiliki kewibawaan (gezag) bagi organisasi yang bernama negara. Kewibawaan negara tersebut sebagai suatu organisasi bersifat politik, tentunya mempunyai kemampuan yang dapat memaksakan kehendaknya kepada para anggota kelompok, yang melanggar aturan tersebut. Oleh karena itu, di dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaannya. Hal ini sesuai dengan karakteristik negara dalam arti formal adalah wewenang pemerintah untuk menjalankan paksaan secara legal (Maksudi,2012;38). Bersamaan dengan konsep negara, maka tidaklah kemudian dapat dipisahkan dengan konsep politik yang selalu mengiringinya, bahkan merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, dikarenakan politik dapat dijadikan sebagai alat legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan kewenangannya. Untuk itu, berkaitan dengan negara, manusia dan politik merupakan konsep-konsep yang selalu saja menjadi bahan pembicaraan dalam setiap pembahasan mengenai kenegaraan. Bahkan, menurut Rodee dkk (2011;2) bahwa Aristoteles (384-322) merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik. Berangkat dari asumsi tersebut, ia mengawali penjelasannya; bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik, karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Hal ini merupakan kecendrungan alami dan tak dapat dihindarkan oleh manusia,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
420
dan hanya sedikit orang yang mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain (Maksudi,2012;9). Dengan demikian, sebagai bintang politik, manusia selalu ingin hidup secara berdampingan dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membentuk suatu komunitas, serta menyerahkan segala citacitanya kepada komunitas tersebut sehingga tercapailah kemudian cita-cita tersebut setelah ikut bergabung dalam komunitas. Dalam membentuk suatu komunitas sebagai wadah daripada kehidupan masyarakat tentunya perlu diawali dengan adanya suatu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan,antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia (Soekanto,2009;55). Sedangkan untuk berlangsungnya suatu proses interaksi sosial tentunya didasarkan berbagai faktor, seperti imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Selain itu, tentunya dalam membentuk suatu komunitas, apalagi sebuah negara pastinya banyak yang kemudian menjadi latar belakangnya. Komunitas mulai dari tingkatannya yang paling sederhana hingga paling besar serta tentunya bersifat kompleks, selalu saja diperlukan manusia sebagai makhluk sosial, terutama dengan tujuan untuk mengatur hidupnya menjadi lebih baik, di samping dengan pertimbangan utama bahwa tujuannya mungkin hanya dapat dicapai jika manusia tersebut kemudian membentuk suatu bangsa dalam arti politis, yaitu negara. Bahkan Zainuddin (1992;xxxi) menyatakan bahwa manusia yang baik adalah seorang warga masyarakat yang baik. Dengan demikian, hanya manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat saja yang kemudian dapat disebut sebagai manusia, sedangkan hanya binatang dan dewa saja yang mungkin dapat hidup sendiri, demikianlah pernyataan Aristoteles. Berdasarkan hal tersebut, ternyata ada kelompok kecil yang memiliki ikatan kuat sebagai satu-kesatuan sosial terkecil dan juga negara yang pada dasarnya ikatan sosialnya jauh lebih lebih renggang apabila dibandingkan kemudian dengan kelompok jumlahnya lebih kecil lainnya, yang juga berada dalam negara itu sendiri. Menurut Soekanto (2009;109-110) bahwa sejalan dengan pembedaan tersebut di atas, maka Carles Horton Cooley mengemukakan perbedaan antara kelompok primer dan kelompok sekunder yang ditulis dalam Social Organisation pada 1909. Kelompok primer dan kelompok sekunder mungkin dapat diterjemahkan dengan istilah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan suatu kelompok yang memiliki kedekatan perasaan di antara para anggotanya, sebaliknya kelompok sekunder merupakan suatu kelompok yang saling tidak mengenal, namun memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Berkaitan dengan kehidupan manusia di dalam kelompok termasuk juga negara, maka secara umum dapat juga dikatakan bahwa seseorang itu tidak dapat menghindarkan diri dari hidup bernegara
I Gusti Ngurah Santika, SPd
421
(Noer,1983;60). Dengan demikian, dapatlah kemudian disimpulkan berkaitan dengan kedudukan manusia bahwa manusia selain sebagai insan Tuhan, ia juga adalah insan sosial, dan insan politik (Winataputra dan Budimansyah,2012;iii). Lebih lanjut, dalam lingkup kehidupannya, manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat, di mana untuk tataran yang begitu besar terjelma dalam suatu negara (Pudyatmoko,2002;1). Ini dikarenakan menurut Syam (1986;201) bahwa masyarakat sebagai bentuk informal suatu bangsa mendahului bentuk formal suatu masyarakat, yang dinamakan negara. Selanjutnya, Thomas Aquinas memberikan tempat yang khusus pada manusia di dalam kedudukannya, tanpa kehendak, tetapi manusia itu adalah sebagai suatu makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Ini disebabkan karena manusia itu mempunyai rasio, dan tak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain (Soehino,1983;59). Oleh karena itu, Sujanto (2012;9) berpendapat bahwa manusia baru menjadi manusia bila ia hidup dengan manusia-manusia yang lain. Dengan demikian, bahwa manusia adalah makhluk yang harus hidup dengan sesamanya dan selalu membutuhkan kerjasama dengan sesamanya (Sarwono,2012;50). Pendapat tersebut adalah sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah Zoon Politicon, manusia merupakan makhluk berkelompok yang tidak dapat hidup sendiri. Walau di mana pun juga, manusia tak dapat hidup seorang diri, dan karena itu harus hidup bersama dan membentuk masyarakat (Van Dijk,2006;1). Adalah suatu kenyataan pula bahwa dalam upaya mempertahankan keberadaannya, manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari manusia yang lainnya (Soemantri,1992;26). Untuk itulah kemudian perlu dibentuk sebuah wadah, seperti dalam bentuk masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi hasrat daripada kodrat manusia sebagai mahkluk sosial. Dengan ikut bergabung dalam suatu masyarakat, maka manusia tersebut akan terlindung, baik dari bahaya yang sewaktuwaktu dapat mengancam diri dan jiwanya, bahkan ancaman tersebut bisa saja datang dari luar maupun dari dalam organisasinya. Selain itu juga, setiap manusia memiliki berbagai tujuan yang tidak dapat dicapai sendirian. Namun, kita dapat mencapai beberapa tujuan dengan bekerja sama dengan orang lain yang mempunyai tujuan yang sama (Dahl,2001;49). Tujuan bersama tersebutlah yang kemudian dijadikan sebagai program, yang hendak direalisasikan oleh masyarakat dalam kehidupannya sebagai bagian daripada negara. Namun, tentunya akan berbeda antara komunitas yang dinamakan masyarakat dengan komunitas yang kemudian dinamakan dengan negara. Apakah yang membedakan konsep tersebut antara yang satu dengan yang lainnya? Sebagai suatu bentuk pergaulan hidup, negara memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
422
hidup lainnya bukan negara. Menurut teorinya, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang paling tinggi dan bersifat khusus sehingga berbeda dengan organisasi kemasyarakatan yang lain (Negara,2008;1). Dengan demikian, ternyata kedudukan daripada organisasi masyarakat berada persis di bawah negara, namun tentunya kedua konsep antara masyarakat dan negara tidaklah begitu saja dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian kata organisasi masyarakat di atas, dapatlah dikutip dari Koentjaraningrat (2005; 132) merupakan suatu istilah yang menekankan pada aspek lokasi hidup dan wilayah, dan konsep kelompok, yang menekankan pada aspek organisasi dan pimpinannya. Untuk lokasi hidup yang dimaksud dengan masyarakat tentunya jelas lebih kecil, jika kemudian dibandingkan dengan wilayah negara, sedangkan pemimpinnya selain sebagai pemegang kekuasaan secara formal, juga telah ditentukan bahwa pemimpin tersebut memegang kekuasaan secara tidak formal, biasanya berada pada satu tangan, seperti kepala desa. Untuk itu, organisasi atau hubungan kerja yang diadakan dalam pergaulan hidup yang kita maksudkan di atas itu kita sebut negara (Kartohadiprodjo,1984;33). Dalam hal ini negara dapat menduduki tempat istimewa dalam masyarakat modern berkat adanya apa yang kita sebut sebagai bangsa (nation) (Amin,1999;1.5). Bangsa sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah bangsa yang bersifat politis, yang mana dalam suatu masyarakat di suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Kemudian setelah mereka bernegara maka terciptalah bangsa. Hal ini tentunya akan berbeda dengan pengertian bangsa dalam arti sosiologis antropologis, yang persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, agama, dan adat istiadat. Atau untuk sekarang konsep ini lebih dikenal dengan istilah etnik, suku, atau suku bangsa. Tentu untuk tercapainya bangsa dalam arti politis, diperlukan proses-proses yang cukup panjang sampai kemudian akhirnya terbentuk suatu bangsa dalam pengertian politis. Bahkan, secara umum kemudian dikenal dua proses terbentuknya bangsa-negara yaitu model ortodok dan model mutakhir (Ramlan Surbakti dalam Winarno,2009;31-32). Pertama, model ortodok yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Contoh bangsa Yahudi berupaya mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Setelah bangsa negara ini terbentuk maka rezim politik (penguasa) dirumuskan berdasarkan konstitusi negara yang selanjutnya dikembangkan oleh partisipasi warga negara dalam kehidupan politik bangsa-negara. Kedua, model mutakhir yaitu berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contohnya adalah kemunculan negara
I Gusti Ngurah Santika, SPd
423
Amerika Serikat tahun 1776. Kedua model ini berbeda dalam empat hal. Pertama, ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Model ortodok tidak mengalami perubahan karena satu bangsa membentuk satu negara. Model mutakhir mengalami perubahan unsur karena dari banyak kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa. Kedua, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa negara. Model ortodok membutuhkan waktu yang singkat saja, yaitu hanya membentuk struktur pemerintahan, bukan pembentukan identitas kultural baru. Model mutakhir memerlukan waktu yang lama karena harus mencapai kesepakatan tentang identitas kultural yang baru. Ketiga, kesadaran politik masyarakat pada model ortodok muncul setelah terbentuknya bangsa-negara, sedangkan dalam model mutakhir, kesadaran politik warga muncul mendahului, bahkan menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa-negara. Keempat, derajat rezim politik dianggap sebagai bagian terpisah dari proses integrasi nasional. Pada model mutakhir, partisipasi politik dan rezim politik merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses integrasi nasional. Keistimewaan negara bangsa dalam arti politis dibandingkan dengan yang lainnya adalah terletak pada kemampunnya untuk mengorganisir serta memaksakan kehendaknya, berupa kekuasaan yang dimilikinya kepada segenap organisasi serta anggota-anggota, yang ada di bawah kekuasaannya. Untuk dapat membedakan antara organisasi negara dengan oraganisasi lainnya, tentunya organisasi negara memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, diperlukan karakteristik berbeda yang kemudian dapat memberikan gambaran nyata. Dapatlah dinyatakan terkait dengan karakteristik daripada suatu negara maka dapatlah dikualifikasikan harus memiliki: 1. A permanen population (penduduk tetap); 2. A defined territory (wilayah tertentu); 3. Government (pemerintah); 4. Capacity to enter into relation with the other states (kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain) (Rudy,2002;23, Ranadireksa,2009;29). Pendapat yang hampir sama juga dinyatakan oleh Nasroen (1986;32, Kusnardi dan Sarigih,2008;105) bahwa negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup, yang mempunyai syarat-syarat tertentu untuk menjadi suatu negara, yaitu harus mempunyai rakyat tertentu, daerah tertentu dan pemerintahan sendiri. Untuk sekarang ini, bahwa suatu negara tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya negara lain. Oleh karena itu, untuk dapat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
424
dikatakan sebagai suatu negara, selain membutuhkan 3 syarat seperti tersebut di atas, maka ada syarat penting lainnya, terutama yang berlaku dalam hubungan internasional, yaitu berupa adanya pengakuan. Sebagai suatu negara yang merdeka tentu tidak akan terlepas dengan negara merdeka lainnya, maka kemudian kita tidaklah dapat menjauhkan diri dari pergaulan dunia internasional. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak adanya perbedaan yang mencolok antara konsep manusia dengan negara, yang dalam kenyataannya jika kita lihat kembali adalah sama-sama membutuhkan pergaulan untuk dapat hidup. Dimana konsep hubungan memegang kata kunci untuk dapat tetap eksis, baik sebagai manusia maupun sebagai negara. Namun, perbedaannya hanya mungkin berkaitan dengan tatacara dalam menjalankan hubungan, antar manusia pastinya akan berbeda dengan hubungan antar negara. Dalam kehidupan internasional kemudian, telah digariskan prinsip-prinsip dasar, agar selanjutnya dapat dikatakan sebagai suatu negara, agar dapat menjalankan hubungannya dengan negara lain. Sehingga, negara lain sebagai suatu lawan dalam berhubungan dengan kita, terlebih dahulu perlu untuk mengakui eksistensi kita sebagai suatu negara. Dengan kata yang lebih sederhana, pengakuan dalam konsep internasional terutama sangat diperlukan untuk menjalani hubungan internasional (international relation). Hubungan internasional terjadi dikarenakan oleh adanya dua faktor utama, yaitu kemajuan industri serta persebaran sumber daya alam yang tidak merata. Ada suatu negara baru ternyata sangat membutuhkan pengakuan dari negara lain dalam dunia internasional. Meskipun menurut Kelsen (2011:316) ternyata ada kekaburan tentang masalah pengakuan. Penyebab kekaburan ini adalah bahwa orang tidak membedakan dengan tegas di antara tindakan yang sepenuhnya berbeda, keduanya disebut pengakuan: yang satu tindakan politik, yang lain tindakan hukum. Namun, untuk dapat dikatakan menjadi suatu negara yang kemudian dianggap memiliki suatu kedaulatan ataupun untuk tetap eksis sebagai suatu negara, maka pengakuan internasional akan keberadaan negara tersebut sangatlah diperlukan, walaupun peristiwa tersebut lebih bernuansa politis ketimbang hukum. Ketidakjelasan daripada konsep pengakuan, untuk menyatakan adanya suatu negara baru merupakan masalah yang utama dalam hubungan internasional, sehingga ke depannya memerlukan kriteria lebih jelas, sehingga selanjutnya dapat mengukur, agar suatu masyarakat nentinya (dalam arti sosiologis) dapat disebut kemudian sebagai sebuah negara (masyarakat dalam arti politis). Jelaslah antara berdirinya negara dengan pengakuan memiliki korelasi yang cukup signifikan. Tidak lain dikarenakan adanya hubungan antara konsep negara dengan pengakuan dari negara lain. Praktek sebagian besar negara menggambarkan adanya pembedaan antara pengakuan de jure dan de facto. Pengakuan de jure berarti bahwa menurut negara yang mengakui, negara atau pemerintah yang diakui
I Gusti Ngurah Santika, SPd
425
secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. Pengakuan de facto berarti bahwa menurut negara yang mengakui, untuk sementara dan secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, bahwa negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta de facto (Starke,2008;187). Kemudian lebih lanjut menurut Kelsen (2011;320) bahwa esensi dari perbedaan ini tidak begitu jelas: secara umum diyakini bahwa pengakuan de jure bersifat final, sedangkan pengakuan de facto hanya bersifat sementara dan oleh sebab itu dapat ditarik kembali. Pengakuan de facto ialah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara (wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). Sedangkan pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan memperoleh pengakuan de jure, maka suatu negara mendapat hak-haknya di samping kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa sedunia (ICCE UIN,2010;86). Jadi dapatlah dikatakan bahwa pengakuan de facto yang bersifat sementara kemudian berubah menjadi pengakuan de jure yang bersifat tetap (Kusnardi dan Sarigih,2008;83). Berikut ini merupakan pendapat penting yang dikemukakan berkenaan dengan masalah pengakuan negara lain terhadap berdirinya suatu negara, menurut Adolf (2002;65) bahwa tanpa mendapat pengakuan ini, negara tersebut sedikit banyak akan mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan negara lainnya. Suatu negara yang belum diakui dapat memberi kesan kepada negara lain bahwa negara tersebut tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban internasional. Pernyataaan tersebut adalah sesuai dengan pendapat Prodjodikoro (1981;19) yang menyatakan bahwa suatu negara tidak mengakui negara baru, menandakan, bahwa tidak ada kepercayaan akan kemampuan negara baru itu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada negara baru itu dalam dunia internasional. Bahkan, menurut Ranadireksa (2009;31) bahwa kualitas negara juga diukur dari sejauh mana suatu negara memiliki kemampuan melakukan hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara timbal balik dengan negara lain. Negara yang tidak memiliki kemampuan membina persahabatan dengan lain bisa berakibat serius bahkan fatal. Tidak tertutup kemungkinan berkembang ke arah campur tangan internasional atas suatu negara yang dinilai telah melakukan kebijakan tertentu yang menimbulkan ketidakstabilan kawasan. Karena pengakuan ini perlu dan penting bagi suatu negara baru. Tidak ada pengakuan dari negara lain paling tidak, akan menyebabkan antara ada dan ketiadaan negara tersebut dalam pergaulan internasional. Ada dua teori pokok mengenai hakekat, fungsi dan pengaruh pengakuan, yaitu :
I Gusti Ngurah Santika, SPd
426
1. Menurut teori konstitutif (constitutive theory), hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional; 2. Menurut teori deklarator atau evidenter (declaratory atau evindentiary theory), status kenegaraan atau otoritas pemerintah baru telah ada, sebelum adanya pengakuan dan status ini tergantung pada pengakuan. Tindakan pengakuan semata-mata hanya pengumuman resmi terhadap situasi fakta yang telah ada (Starke,2008;177). Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan kemudian bahwa selain ada unsur rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, ada unsur pengakuan dari negara negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan, bukan unsur yang mutlak (Winarno,2009;37). Selanjutnya, lebih jauh lagi terkait dengan organisasi yang bernama negara, kemudian jika kita tinjau dari dalam, maka negara pada dasarnya memiliki sifat-sifat yang dapat membedakannya dengan organisasi lainnya bukan negara. Sifat-sifat khusus ini merupakan manifestasi daripada kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja. Dengan demikian, seperti dinyatakan di atas, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan antara organisasi antara negara dengan lainnya, namun pada umumnya dapatlah dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua. Pengartiannya dari ketiga sifat negara tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Sifat memaksa. Agar semua peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan secara fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. 2. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
427
3. Sifat mencakup semua (all-scompaassing, all-embracing). Semua peraturan perundang-undangan (misalnya membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali (Budiardjo,2008;50). Sifat-sifat negara sebagaimana disebutkan di atas, merupakan menifestasi dari kedaulatan negara adalah untuk mencapai tujuan bersama, yang telah ditetapkan bersama anggota masyarakat dalam suatu negara tersebut. Tujuan sama dimaksudkan tersebut adalah sebagai gambaran dari kehendak bersama, sampai akhirnya mewakili suatu cita, atau yang biasanya disebut dengan cita bersama. Berikut ini merupakan berbagai macam cita negara sebagai wadah cita bersama, antara lain : 1. Cita negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat); 2. Cita negara kekuasaan (Machstaats); 3. Cita negara kerakyatan (Volkstaats); 4. Cita negara kelas (Klassen staat); 5. Cita negara liberal (Liberal staat). 6. Cita negara totaliter kanan (Totaliteire staat van recht); 7. Cita negara totaliter kiri (Totaliteir staat van links); 8. Cita negara kemakmuran (Welvarsstaat) (Sibuea,2010;7). Selain, tentang konsep cita negara (staatsidee) sebagaimana dimaksud di atas, tentunya konsep negara tidak dapat dipisahkan dengan konsep hukum yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara, agar dapat tercapai tujuan daripada negara hukum. Memang dapatlah kemudian dikatakan bahwa dalam kehidupan bernegara, hukum ternyata sangat dibutuhkan, terutama untuk mengatur kehidupan agar ketertiban dan kedamaian selanjutnya dapat tercipta. Dapatlah kemudian dibayangkan bahwa suatu organisasi besar yang bernama negara tersebut, ternyata tidak ada hukum yang mengaturnya. Hanya dengan adanya hukum, negara mendapatkan legitimasinya, untuk mengatur anggota-anggota yang bertempat tinggal di negara tersebut, namun tentunya perlu untuk digaris bawahi, bahwa hukum yang dibentuk kemudian merupakan kehendak rakyat sendiri. Hukum akan menjadi sebuah instrumen pembenaran terhadap segala tindakan negara, bahkan dapat memaksakan semua kehendaknya, agar selanjutnya dituruti rakyat yang bertempat tinggal di bawah kedaulatannya. Dengan demikian, dapatlah kemudian dikatakan bahwa hukum ternyata
I Gusti Ngurah Santika, SPd
428
memiliki berbagai fungsi, seperti sebagai sarana kontrol sosial (social control), perekayasan sosial (social engineering), sebagai simbol, sebagai alat politik, sarana penyelesaian sengketa, pengendalian sosial, dan pengintegrasi sosial. Selain adanya kaidah hukum, dalam kenyataannya juga terdapat kaidah lainnya, yang secara sosiologis tidak kalah pentingnya pula, untuk kemudian mengatur kehidupan masyarakat. Bahkan dapat saja bahwa kaedah tersebut lebih diikuti oleh masyarakat, dikarenakan memang sudah berakar dan tumbuh subur dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, hendaknya hukum yang memiliki posisi paling tinggi sebagai instrumen negara, haruslah pula sesuai dengan kebiasaan hidup masyarakat yang memang sudah mengakar. Sebab jika hukum yang dibentuk oleh negara ternyata berlainan sekali dengan kebiasaan yang sebenarnya sudah lama hidup di tengahtengah masyarakat, maka hukum tersebut tidak akan dapat berlaku dengan efektif. Dikarenakan, hukum tersebut ternyata tidak mendapatkan dukungan secara sosiologis dari rakyat, sehingga kemudian hanya akan menonjolkon sisi kerasnya saja. Hal tersebut dikarenakan, menurut Soerjono Soekanto (1982;49) bahwa perubahan yang ingin dicapai melalui hukum tidak dapat diikuti oleh masyarakat. Dengan demikian, corak hukum pun lebih menampakan segi-segi ketertiban daripada kebebasannya (Soekanto,2009;210). Hukum sebagai kaedah memang sangat penting bagi kehidupan, namun dalam kenyataannya juga terdapat kaedah lainnya yang kemudian dijadikan tumpuan pula dalam kehidupan di masyarakat, bahkan untuk hidup bernegara yang tidak kalah pula pentingnya dengan kaedah hukum, yaitu adanya norma-norma sosial yang juga hidup dalam masyarakat sendiri. Soekanto (2009;183) memberikan empat pengertian norma, di mana fungsi norma tersebut adalah sama, yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Norma sebagaimana dimaksud, yaitu (1) cara (usage) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan, (2) kebiasaan (folkways) adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, (3) tata kelakuan (mores) merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur, (4) adat istiadat (custom) adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Ada sanksi penderitaan bila dilanggar. Mengikatnya norma-norma tersebut secara sosiologis adalah berbeda antara satu norma dengan norma lainnya. Bahkan mengenai sifat kaedah dapatlah dibedakan menjadi dua, yang pada dasarnya bersifat imperatif dan fakultatif. Di mana kedua sifat kaedah tersebut tercermin dalam hubungannya dalam masyarakat, misalnya untuk kaedah yang bersifat imperative dapat digolongkan menjadi hukum publik, seperti pidana, administrasi negara, tatanegara dll, sedangkan untuk hukum bersifat fakultatif, yaitu masuk dalam hukum perdata. Namun dapatlah dikatakan bahwa kaedah/norma-norma tersebut adalah sangat penting, tidak hanya dalam pergaulan di
I Gusti Ngurah Santika, SPd
429
masyarakat, namun juga dalam kehidupan bernegara. Sehingga dalam pergaulan hidup masyarakat kaedah-kaedah/norma-norma tersebut kemudian dijadikan tumpuan dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan dikatakan bahwa setiap norma tersebut dalam bidang masing-masing biasanya sudah mempunyai sanksi sendiri (Prodjodikoro,2008;13). Semua hal tersebut tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan hukum melalui budaya hukum (culture), di samping adanya substance (isi atau materi) maupun structure (aparat penegak hukum). Namun, dapatlah dikatakan bahwa norma merupakan masalah yang bersifat utama dalam melakukan fungsi perekayasaan masyarakat (social engineering). Menurut Mahmud MD (2010;274) bahwa norma dapat dibedakan menjadi 4 macam norma, yaitu: 1. Norma Agama; 2. Norma Kesusilaan; 3. Norma Kesopanan; 4. Norma Hukum. Berikut di bawah ini merupakan sedikit paparan terkait dengan pengertian dari masing-masing norma-norma seperti tersebut di atas, yang kemudian akan disajikan kembali secara garis besarnya sehingga dapat diharapkan untuk mendapatkan sedikit pemahaman. 1. Norma agama atau kepercayaan. Mertokusumo (1996;5) menyatakan bahwa kaedah kepercayaan atau keagamaan ditujukan kepada kehidupan beriman. Kaedah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada tuhan dan kepada dirinya sendiri. Sumber atau asal kaedah ini adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Bahkan menurut Soekanto (2009;242) bahwa kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia menganut kehidupan beriman. Tuhan sendirilah yang mengecam pelanggarnya dengan sanksi-sanksi, bahkan sanksi yang diancamkan adalah sanksi di akhirat. Jika kemudian dalam kenyataannya kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kepercayaan atau agama, Tuhan dalam hal ini akan memberikan phala yang membuat kita tidak akan bahagia diakhirat nantinya. Terlihatlah kelemahan dari norma agama ini, karena sanksi yang diberikan adalah ketika kita sudah berada di dunia lain. Namun, dapat saja
I Gusti Ngurah Santika, SPd
430
orang-orang yang pada dasarnya tidak percaya pada Tuhan, tidak akan takut terhadap sanksi diancamkan, apalagi kalau memang orang tersebut tidak memiliki kepercayaan terhadap agama (orang yang tidak beragama). 2. Norma kesusilaan. Kaedah kesusilaan berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Asal atau sumber kaedah kesusilaan adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom. Kalau kaedah-kaedah kesusilaan tadi termasuk kaedah-kaedah pribadi yang khusus mengenai pematokan yang menyangkut hati nurani (geweten) atau patokan-patokan mengenai hasrat-hasrat rohaniah yang tidak dapat atau tidak perlu kelihatan (Soekanto dan Purbacaraka,1993;15). Jadi batin kita akan memberikan sanksi terhadap kesalahan yang kita perbuat (otonom). Norma bersifat otonom, dalam arti norma itu datangnya dari dalam diri seseorang (Indrati,2007;25). Walaupun mungkin saja nantinya orang lain tidak tahu tentang kesalahan yang kita perbuat, namun toh kita tidak akan dapat berlari dari suara hati kita, karena suara hati itulah yang akan selalu mengingatkan kita akan kesalahan yang pernah kita perbuat. Dengan demikian, norma kesusilaan pada dasarnya merupakan norma yang sifanya paling hakiki, bahkan dapat dikatakan bahwa merupakan norma yang paling tua (norma ini ada sejak manusia ada). Tidak lain dikarenakan bahwa kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani (conscience) yang bersih (Soekanto,2009;242). Namun, kelemahan dari norma ini adalah suara batin, yang tanpa adanya suatu imbangan berupa pengetahuan maka suara hati tidak akan mampu membangkitkan kebenaran hati nurani kita. Dengan demikian, untuk dapat membangkitkan suara batin kita terhadap kebenaran, maka diperlukan pengetahuan yang kemudian dapat memberikan keseimbangan. Sebab jika kita tidak memiliki tentang pengetahuan tentang mana yang benar dan salah, tentunya juga akan sangat berpengaruh pula terhadap hati nurani kita. Maka, penulis menyarankan agar selalu mengasah hati nurani/batin dengan terus belajar, sehingga pengetahuan yang benar akan membantu hati nurani untuk selalu membisiki kita akan kesalahan yang pernah diperbuat. Dengan bertambahnya pengetahuan akan kebenaran nah!!! kemudian disitulah hati nurani berdasarkan pengetahuan akan kebenaran yang ia ketahui akan mampu mengawal kebenaran tersebut lewat bisikan-bisikan halus.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
431
3. Norma kesopanan. Kaedah kesopanan didasarkan atas kebiasaan, kepatutan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Kekuasaan masyarakat secara tidak resmilah yang kemudian akan mengancam dengan sanksi bila kaedah sopan santun itu dilanggar. Yang memaksakan kepada kita adalah kekuasaan di luar diri kita (heterenom). Suatu norma hukum itu bersifat heteronom, dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri seseorang (Indrati,2007;25). Kaedah ini lebih sempit daya lakunya, tergantung daripada tempat serta masyarakat tempat norma tersebut hidup. Pelanggaran terhadap norma tersebut, akan dicela oleh masyarakat dimana kelakuan tersebut dilakukan padahal seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan keyakinan masyarakat setempat. Namun, mungkin jika kelakukan tersebut dilakukan di tempat yang masyarakatnya berlainan, bisa saja perbuatan tersebut tidaklah bertentangan dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Maka, berkaitan dengan norma kesopanan sangat tergantung pada tempat dimana norma tersebut berlaku, sehingga untuk menghindari diri agar tidak melanggar suatu norma kesopanan, terlebih dahulu kita harus menyelediki bagaimanakah adat istiadat di sana, sehingga nantinya kita dapat menyesuaikannya terlebih dahulu. Contoh-contoh yang kemudian dapat diberikan terkait dengan norma kesopanan misalnya, cara berbicara, pakaian, bahasa, dll. 4. Norma hukum Suatu pengertian yang mungkin perlu dikemukakan di sini adalah berkaitan dengan hukum yang dalam kata Latin ius, Belanda recht, Perancis droit, dan Jerman Recht dapat berarti hak dan hukum (Marzuki,2009;88). Menurut Mertokusumo (1996) bahwa pengertian hukum dalam literatur Belanda disebut objekctief recht karena umum dan mengikat. Kata recht artinya dibagi menjadi dua yaitu objectief recht yang berarti hukum dan subjectief recht berarti hak dan kewajiban. Hal mana adalah sesuai dengan pendapat (Prodjodikoro (2008;22) yang menyatakan bahwa kata recht mengandung dua arti, yaitu pertama sebagai hak atau wewenang dan kedua sebagai peraturan hukum. Memang berkaitan dengan pengertian hukum sampai sekarang masih belum dapat ditemukan definisi yang memuaskan. Apa yang ditulis oleh Kant lebih dari 150 tahun yang lalu : Noch suchen die juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von rech masih tetap berlaku (Aperldoorn,2011;1). Bahwa para sarjana masih berusaha untuk mencari definisi hukum yang tepat sejak 150 tahun yang lalu. Tidak ditemukannya definisi hukum, dikarenakan hampir semua ahli hukum memberikan definisi tentang hukum yang satu sama lainnya berbeda. Dikarenakan hukum itu sendiri meliputi banyak segi dan bentuk sehingga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
432
luaslah hukum itu yang meliputi segala hal yang tentunya tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Menurut penulis bahwa hukum adalah semua peraturan baik tertulis (written) maupun yang tidak tertulis (unwritten), yang mengatur kehidupan masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang yang bersifat mengikat, apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi tegas dan memaksa bagi pelanggarnya. Dengan demikian, maka untuk dapat dikatakan bahwa sesuatu adalah hukum, maka harus dilihat unsur-unsurnya, seperti adanya peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat (berisi hak dan kewajiban), peraturan tersebut dibentuk oleh badan-badan/lembaga-lembaga resmi yang berwajib, peraturan tersebut bersifat memaksa, sifat memaksa sebagai dimaksud tersebut tercermin adanya sanksi yang tegas terhadap orang yang melanggar peraturan tersebut oleh organ negara. Untuk mengenal hukum itu kita harus dapat mengenali ciri-ciri hukum, yaitu adanya perintah dan/atau larangan, perintah dan/atau larangan itu harus dipatuh ditaati setiap orang (Kansil dan Christine,2002;12). Sifat hukum adalah mengatur (regelen) dan memaksa (dwingen recht), yang di dalamnya terdapat sifat-sifat yang isinya suruhan (gebod), larangan (verbod), kebolehan (mogen). Yang diatur oleh hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum sendiri dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban guna bertindak menurut tata cara yang ditentukan oleh hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah manusia (natuurlijk person) dan badan hukum (recht person). Hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor, yaitu faktor-faktor yuridis, filosofis, dan sosiologi (Soekanto,2009;171). Ketiga faktor tadi memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan (etis), kegunaan (utility), dan kepastian hukum (rechtszekerheid). Seperti diketahui dalam ilmu hukum itu didapatkan pembagian hukum ke dalam dua macam, yaitu hukum privat (sipil) dan hukum publik (Mahmud MD dan Marbun,2000;18). Berikut ini merupakan perbedaan daripada kedua macam hukum di atas, bahwa. Bahwa Hukum privat titik berat berada pada kepentingan suatu orang manusia, sedang ada perhubungan hukum lain (publik) yang keadaannya sedemikian rupa, bahwa titik berat berada kepada kepentingan orang-orang manusia yang merupakan suatu kumpulan yang kepentingannya nampak lain dari pada kepentingan suatu orang manusia yang tertentu. Sudah barang tentu dalam keadaan yang tersebut pertama itu lebih terserah kepada kemauan seorang manusia yang tertentu itu untuk menetapkan, apakah hak dalam perhubungan hukum harus dilaksanakan atau tidak, oleh karena titik berat dari kepentingan yang bersangkutan adalah terletak kepadanya. Sedang dalam keadaan yang tersebut kedua kali tadi, haruslah ditanyakan kepada gerombolan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
433
orang-orang manusia atau kepada wakilnya tentang ya atau tidak dilaksanakan hakhak yang ada pada perhubungan itu, oleh karena titik berat dari kepentingan yang bersangkutan terletak pada orang-orang banyak itu sebagai kumpulan (Prodjodikoro,1992;5-6) (kursif penulis). Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa antara konsep negara memiliki suatu hubungan yang sangat erat dengan konsep hukum. Oleh karena itu, dapatlah kemudian diperoleh suatu kesimpulan mengenai hubungan antara hukum dan negara, yaitu sebagai berikut. Negara sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan, sedangkan hukum berfungsi sebagai batas-batas negara dalam menjalankan kekuasaannya. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara popular, kesimpulan ini barangkali dapat dirupakan dalam slogan: hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman (Ragawino,2007;12). Dengan demikian, posisi hukum dan negara berada dalam satu rel yang sama, dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan negara, yang telah diletakan dan dicantumkan dalam konstitusinya sebagai pencerminan hukum negara paling tinggi. Hukum menjamin daripada kelangsungan negara, terutama berkaitan dengan legitimasinya dalam bertindak, karena hukum sendiri pada dasarnya merupakan batasan bagi negara, sedangkan hukum membutuhkan negara untuk menegakannya. Tidak lain dikarena hukum tidak akan dapat menegakan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari negara. Ini kemudian dapat dimengerti, karena pada jaman modern sekarang ini tidak ada negara tanpa hukum dan hampir tidak ada hukum tanpa negara (Prodjodikoro,1981;47). Kekuasaan negara yang tanpa dibatasi oleh hukum, akan menjadi potensi bahkan meluas sehingga berimplikasi kepada kesewenang-wenangan yang kemudian pada gilirannya akan menindas rakyat. Usaha mengurangi serta membatasi kekuasaan itu akan berjalan efektif apabila dilakukan oleh hukum, sebab hukum dan kekuasaan merupakan dua institusi yang berhubungan sangat erat satu sama lain (Soemantri,1992;73). Untuk itu, kekuasaan itu perlu diatur sedemikian rupa agar tidak menunjukan kesewenang-wenangan serta arogansinya, yang kemudian tercermin oleh penyelenggara negara dalam melakukan tugas kenegaraannya, hanya dengan hukumlah kekuasaan dapat batasi. Memang hukum dalam bentuk yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat (Marzuki,2009;83). Namun, jika hukum tersebut ternyata tidak
I Gusti Ngurah Santika, SPd
434
memiliki sebuah organisasi kekuasaan yang berfungsi untuk mempertahankannya, maka hukum hanya akan merupakan suatu idealitas belaka, sehingga akan semakin jauh daripada realitas, yang sebenarnya mungkin menjadi tujuan utama hukum tersebut. Sehingga hukum dan kekuasaan haruslah berjalan secara beriringan dan kemudian saling bergandengan tangan, untuk mencapai tujuan bersama yang sebelumnya telah digariskan, sehingga posisi keduanya tidak saling mendahului dan satu sama lainnya. Oleh karena itu, seharusnya kekuasaan dan hukum berada pada kedudukan sederajat, sehingga di antara keduanya tidak ada yang mendominasi antara satu dengan lainnya. Dikarenakan, di antara keduanya harus saling mendukung untuk mencapai tujuan daripada negara, kemudian seraya menghindari daripada faktor-faktor negatif yang dibawa oleh kekuasaan, sehingga hanya hal positif dari kekuasaanlah yang akan menonjolkan dirinya. Sehingga kekuasaan yang hanya didasari oleh hukum akan memiliki legititimasi di hadapan rakyat. Tanpa adanya legitimasi dari rakyat, maka kekuasaan tersebut tidaklah dapat dikatakan bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena keadilan yang tersimpul dan menjadi tujuan dari hukum harus mendapatkan dukungan sepenuhnya rakyat yang berdaulat. Partisipasi rakyat lewat keterlibatannya secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya dalam pembuatan hukum, merupakan bentuk nyata daripada adanya legitimasi rakyat terhadap kedudukan penguasa, yang selanjutnya akan membentuk peraturan, hal mana pada dasarnya peraturan tersebut mengikat rakyat nantinya ke depan. Pendapat tersebut adalah sangat sesuai dengan negara yang mengaku menganut demokrasi perwakilan, yang pada dasarnya meletakan kehendak rakyat sebagai sumber utama daripada keabsahan kedudukan penguasa dalam melakukan berbagai tindakannya. Pernyataan di atas adalah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Erwin (2011;280) yang menyatakan bahwa kekuasaan itu pada hakekatnya merupakan upaya untuk menemukan keadilan dan hukum yang adil di masyarakat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan. Dengan demikian, hukum, masyarakat dan keadilan merupakan rangkaian dalam kehidupan negara yang tidak mungkin dapat untuk dipisahkan satu di antara lainnya. B. Pengertian Negara Hukum Kata negara hukum (rechstaat) ternyata sering dilawankan dengan kata negara kekuasaan (machtstaat). Menurut Fuady (2010;21) bahwa jika berbicara tentang negara hukum berarti berbicara tentang konsep negara yang berdasarkan hukum. Jadi hukumlah yang menjadi titik tolak serta dasar dalam kehidupan bernegara sebagai suatu negara hukum, sehingga tanpa adanya hukum yang mendasari tindakan daripada negara, maka tidaklah mungkin untuk dapat negara tersebut dianggap sebagai negara hukum. Penulis memahami istilah negara hukum merupakan suatu pengertian umum yang dapat dikaitkan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
435
dengan berbagai konotasi. Terkait dengan negara hukum, Fadjar (2005;6) kemudian memberikan pengertian daripada negara hukum, yaitu: Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (state the not governed by men, but by law). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undangundang negara. Namun, jika disimak kembali berkaitan dengan pengertian yang diberikan di atas tersebut, maka penulis merasa keberatan atas pengertian negara hukum sebagaimana maksud di atas. Dikarenakan pengertian yang diberikan terkait negara hukum, ternyata hanya menjadikan undang-undang sebagai titik tolak serta kemudian dijadikan patokan dalam kehidupan bernegara, tanpa memperhatikan adanya aturan hukum tidak tertulis yang benar-benar hidup di dalam masyarakat. Dengan hanya mendasarkan diri kepada undangundang saja, maka dapat saja kemudian kita dapat terjebak dan tergelincir ke dalam pengertian negara hukum yang bersifat formal. Dikarenakan undang-undang selalu dijadikan sebagai pembenaran (justification) oleh negara dalam melakukan setiap tindakannya, yang sejatinya tindakan tersebut adalah tidak sesuai, bahkan bertentangan secara diametral dengan hukum yang tidak tertulis, terutama nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengan masyarakat (living law). Hal mana adalah sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh Rindjin (2009;279) bahwa prinsip negara hukum bukanlah sekedar dalam arti formal, di mana tindakan para penyelenggara negara semata-mata berdasarkan pada hukum tertulis dan tugas negara hanya menjaga ketertiban dan keamanan jangan sampai terjadi pelanggaran (kursif penulis). Dengan demikian, penulis menyarankan agar negara hukum yang dibentuk kemudian, tidak saja mendasarkan dirinya hanya kepada undangundang belaka, namun juga kepada hukum yang benar-benar dapat mencapai keadilan (just law), tanpa hukum yang adil di samping dapat menjamin tindakan negara dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum yang hidup di tengah-tengah rakyat, maka hukum itu hanya mendatangkan petaka bagi rakyat dimana temapt hukum itu berlaku. Dasar pemikiran tersebut dinyatakan tidak lain dikarenakan bahwa hukum adalah kehendak rakyat, sedangkan yang menjadi sasaran dan pengguna jasa hukum sendiri adalah rakyat. Karena
I Gusti Ngurah Santika, SPd
436
tanpa itu, maka bisa saja segala tindakan daripada aparat negara, dengan menjadikan undang-undang hanya sebagai sarana legitimasi, untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, jika hukum yang kemudian dibuat oleh negara ternyata bertentangan dengan rasa keadilan rakyat, keberlakuan hukum tersebut hanya akan dipaksakan oleh penguasa (machtstheorie), bukan dilaksanakan atas kemauan rakyat sendiri dikarenakan adanya pengakuan (anekernnungstheorie) akan kegunaannya dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, jika hukum yang dibuat kemudian oleh negara, ternyata sesuai dengan kehendak rakyat serta membawa manfaat yang besar bagi rakyat, maka kekuatan daripada keberlakuan hukum tersebut adalah disebabkan karena kebergunaannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga hukum tersebut akan mendapatkan dukungan berupa legitimasi daripada rakyat, yang kemudian pada akhirnya akan mampu mencapai cita-cita dan tujuan yang diharapkan dari kelahiran hukum tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa untuk mendukung tercapainya suatu negara hukum, maka hukum yang dibuat oleh perlengkapan negara perlulah kemudian mendapat dukungan luas dari rakyat, oleh karena tanpa adanya dukungan rakyat, apa yang kemudian menjadi tujuan hukum tersebut akan sulit untuk dicapai. Oleh karenanya, maka patut untuk dikutip pendapat dari Rahardjo (2006;13) tentang adanya hubungan masyarakat dengan ketertiban sebagai dari salah satu tujuan hukum, yaitu sebagai berikut. masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa adanya suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut dengan ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Bahwa kaidah-kaidah pada umumnya dan kaidah hukum pada khususnya, sebetulnya telah mengikat manusia sejak dia dilahirkan di dunia. Dan kiranya adalah tepat kemudian sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Cicero kira-kira 2000 tahun lalu, bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada kehidupan bersama, di sana ada hukum (Soekanto,2009;204). Dengan demikian, dapatlah dikatakan jika manusia sudah ada dalam lingkungan manusia atau dalam kenyataannya sudah ada manusia lain yang berada di sampingnya, maka di sanalah kemudian akan lahir hukum. Hukum yang lahir tersebut, bertugas mengatur berbagai kepentingan dari orang-orang tersebut sebagai suatu
I Gusti Ngurah Santika, SPd
437
masyarakat, dengan tujuan agar kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut, tidak terjadi benturan satu sama lain. Jika, ternyata hanya ada satu orang saja dalam suatu pulau misalnya, maka belumlah perlu ada hukum, namun jika selanjutnya sudah ada manusia lain yang datang ke sana, maka hukum diperlukan untuk mengaturnya, agar kemudian tidak terjadi benturan dari berbagai kepentingan. Dengan demikian, masyarakat, hukum, dan ketertiban merupakan hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadi negara hukum. Hukum yang mengatur masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mencapai ketertiban, namun hukum terlahir kemudian dari masyarakat yang pada dasarnya mampu melahirkan ketertiban pula. Sehingga tujuan hukum adalah untuk mendekatkan masyarakat dengannya. Kemudian lebih lanjut berkaitan dengan pengertian negara hukum, merujuk pendapat dari Winarno (2009;117) bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekurangan dari pengertian tersebut di atas adalah tidak adanya rakyat sebagai salah suatu unsur dalam negara hukum, padahal diketahui bahwa masyarakat merupakan salah satu sasaran daripada lahirnya hukum, seperti disebutkan di atas. Berdasarkan pengertian yang telah diberikan di atas, maka untuk lebih memperjelas kembali, perlu kiranya untuk merujuk daripada pendapat Prodjodikoro (1981;37) yang menyatakan bahwa istilah negara hukum, yang berarti suatu negara di mana di dalam wilayahnya: 1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenangwenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan; 2. Semua orang-orang penduduk perhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Definisi negara hukum seperti tersebut di atas, menurut penulis adalah sudah sesuai dengan apa yang memang dimaksudkan, namun ternyata maksud tersebut tidak ditemukan oleh definisi-definis sebelumnya yang dibuat oleh para ahli. Bahkan pengertian negara hukum yang diberikan di atas, ternyata selain adanya rakyat (warga negara) sebagaimana yang memang penulis maksudkan seperti di atas, kemudian oleh Prodjodikoro
I Gusti Ngurah Santika, SPd
438
memperluasnya sehingga mencakup juga orang asing, yang kedua-duanya tersebut tersimpul dalam kata penduduk. Juga di dalam pengertian negara hukum tersebut terdapat pemerintah dan lembaga-lembaga lain, dalam melakukan tindakannya harus selalu sesuai dengan hukum berlaku serta dapat bertanggungjawab secara hukum. Dalam hubungan ini maka alat perlengkapan negara harus menaati norma hukum (Sudarto,1986;22). Dengan demikian, selanjutnya para penyelenggara negara terutama dalam melaksanakan tindakannya harus selalu berdasarkan atas asas legalitas, tanpa adanya suatu hukum yang pada dasarnya mendahului tindakan dari aparat negara tersebut, niscaya tindakan aparat negara tersebut adalah bertentangan dengan konsep daripada negara hukum itu sendiri. Hal mana adalah sesuai sekali dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fadjar (2005;58) bahwa asas legalitas merupakan unsur atau elemen yang utama dari sebuah negara hukum sebab memang negara hukum adalah suatu negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh orang-per orang atau government by law not by men. Menurut Ridwan (2011;90-91) bahwa pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak negara. Di Inggris terkenal ungkapan No taxation without representation, tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di Amerika ada ungkapan: Taxation without reprentation is robbery, pajak tanpa (persetujuan) parlemen adalah perampokan. Jadi, hukumlah yang kemudian melahirkan dasar bagi tindakan aparat negara karena kedudukan dan fungsinya sebagai pedoman. Dikarenakan bahwa tanpa adanya hukum sebagai acuan utama dalam bertindak bagi penyelenggara negara, tentunya akan menimbulkan penyelewengan, bahkan bisa saja kemudian menimbulkan ekses-ekses daripada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dengan demkian, diharapkan bahwa hukum mampu membatasi kekuasaan (politik), tanpa takut apabila kemudian hukum itu sendiri dihadapkan pada kekuasaan. Dasar atau asas kehidupan bernegara tersebut sebenarnya telah memberikan gambaran yang cukup kepada kita bahwa hukum pada dasarnya senantiasa akan selalu berhadapan dengan kekuasaan (politik). Namun, tentunya hukum harus senantiasa dikedepankan atau lebih diutamakan dari dimensi lain (terutama dimensi politik) manakala menghadapi kekuasaan (Bisri,2010;13). Namun, dapatlah diketahui kemudian bahwa dalam kenyataannya dimensi politiklah yang lebih mendominasi hukum, sehingga selanjutnya apa yang sesungguhnya sudah menjadi norma hukum, ternyata dapat dimentahkan kembali, terutama dengan tafsiran politik. Adanya konsep seperti itu kemudian menimbulkan implikasi bahwa hukum tanpa ada suatu dukungan kekuasaan politik, maka dapat dipastikan bahwa hukum akan mengalami kesulitan dalam menerapkannya di lapangan. Walaupun pada dasarnya suatu keputusan politik, yang kemudian sudah menjadi hukum,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
439
selanjutnya tidak boleh lagi ditafsirkan kembali secara politik, namun demikianlah kenyataannya. Untuk itu, Indonesia yang juga dari dulu menyatakan dirinya sebagai suatu negara hukum, harus selalu mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip negara hukum. Bahwasanya sampai sekarang Indonesia masih berusaha untuk menegakan hukum, walaupun belum dapat sepenuhnya terwujud, namun telah menjadi suatu keharusan untuk mencapainya terutama dengan mendasarkannya pada hukum yang adil (just law). Dapat dikatakan bahwa ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai sebuah negara hukum, dalam setiap langkah dan kebijakan negara harus berdasar atas hukum (Rindawan,2010;86). Sebagai pegangan yang kuat tentunya kita harus memiliki sebuah cita yang kemudian dapat mengarahkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai keadilan, prinsip sebagaimana dimaksud di atas adalah cita negara hukum. Cita negara hukum adalah cita bahwa penyelenggaraan negara termasuk pemerintahannya harus selalu dilandaskan dan berpegang pada aturan yang baik dan berkeadilan (Kesowo,2012;6-7). Jadi, keadilan sebagai tujuan daripada aturan hukum yang baik, merupakan salah satu prinsip dasar yang memang harus dicapai kemudian oleh setiap negara yang mengaku hendak mewujudkan negara hukum. Karena hukum yang dapat mencapai keadilan akan mampu menopang tegaknya hukum sebagai yang tertinggi (supremacy of law). Tegaknya hukum atau the rule of law harus berarti tegaknya hukum yang adil atau tegaknya keadilan (Kirdi,1985;10). Karena itu, pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi (Latif,2010;50). Keadilan sendiri dibagi oleh Aristoteles dalam bukunya retorica menjadi dua, yaitu keadilan distributif (justitia distributiva) dan keadilan komutatif (justitia comutativa). Jadi konsep keadilan, merupakan prasyarat utama dalam mencapai supremasi hukum, tanpa hukum yang berkeadilan maka supremasi hukum (supremacy of law) tidak dapat diharapkan akan bisa terwujud kemudian. Dengan demikian supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di negara kita (Husni,2007;8). Oleh karena itu, supremasi hukum perlu untuk diwujudkan dalam kehidupan bernegara, maka diperlukan pedoman yang tepat agar selanjutnya dapat menjelaskan apakah sebenarnya yang disebut dengan supremasi hukum itu. Mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi (Asshiddiqie,2011;222). Dengan adanya supremasi hukum yang kemudian berwujud konstitusi akan dapat memberikan sedikit penjelasan bahwa kedudukan hukum merupakan yang tertinggi dalam suatu negara, dengan kata lain bahwa tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan hukum tersebut. Untuk itu, supremasi hukum tidak memandang apapun maupun siapapun, selain hanya bertujuan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
440
untuk tegaknya hukum yang berdasarkan atas kebenaran dan keadilan substansial yang perlu diperjuangkan. Bahkan, ada pepatah Romawi yang menyatakan fiat justitia roet coelum, walaupun langit runtuh hukum harus tetap ditegakan. Bahkan tegaknya supremasi hukum di tanah air ini merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang penting dan mendesak (crucial) untuk dilaksanakan dan diperjuangkan selama ini pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru (Sutiyoso,2006;106). Jika kita kembali ke belakang melihat sejarah perjalanan hukum di Indonesia, maka tidak heran kita sampai sekarang tetap mendambakan supremasi hukum. Dalam prakteknya, selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, yang terjadi adalah supremasi kekuasaan, bukan supremasi hukum (Nazriyah,2010;28). Negara hukum adalah negara yang mampu menegakan supremasi hukum bertujuan untuk menegakan kebenaran dan keadilan substansial dan tidak ada kekuasaan apapun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Negara hukum kemudian dapat ditandai dengan adanya ciri sebagai berikut: (1) Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur, dan pendidikan; (2) Peradilan yang bebas, dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan apapun; (3) Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya (Rukmini,2009;155). Untuk tercapainya negara hukum, maka perlu ada aspek-aspek ataupun kriteria untuk mengukur apakah suatu negara sudah mencapai negara hukum atau belum. Ada tiga aspek yang kemudian dicakup oleh adanya ketentuan ini. Aspek pertama adalah persamaan di muka hukum. Aspek kedua yaitu perlindungan hukum yang sama, dan aspek ketiga adalah adanya perlindungan terhadap diskriminasi (Nasution,dkk,2001;200). Oleh karena itu, menurut pendapat Erwin (2009;52) bahwa kesamaan demikian itu hanya terbantu oleh sistem politik yang menjamin partisipasi warga secara aktif dalam pengambilan keputusan. Kemudian akan tercapainya, keadaan sama derajat dari manusia ini lazimnya dipernyatakan dengan kesamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dan kesamaan terhadap kesempatan (equality for the opportunity) (Pamudji,1985;14). Bahkan jelas sekali bahwa untuk tegaknya supremasi hukum dalam mencapai negara hukum yang didambakan, maka harus ditentukan pula bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Bahkan terkait dengan konsep kesamaan untuk di Indonesia, menurut pendapat Soemantri (1992;8) yang kemudian menyatakan artinya bahwa setiap orang warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, undang-undang dasar kita tidak mengenal adanya golongangolongan warga negara (Subekti,1994;14). Perlulah dinyatakan bahwa tujuan akhir dari paham negara hukum ini adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap
I Gusti Ngurah Santika, SPd
441
hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa (Abdullah,2005;11). Dikarenakan pada dasarnya kekuasaan adalah cenderung untuk disalahgunakan oleh penguasa, tentunya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) kemudian akan menimbulkan penindasan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah ciri daripada negara hukum yang demokratis. Untuk mencapai negara hukum yang demokratis, tentunya kemudian perlu diawali dengan adanya pembangunan hukum, karena dengan adanya pembangunan hukum, merupakan suatu keniscayaan untuk tegaknya supremasi hukum serta tegaknya keadilan akan tercapai, yang pada akhirnya cita-cita daripada negara hukum akan betul betul dapat terwujud nantinya. Seperti diketahui sebelumnya bahwa ranah pembangunan hukum menurut Lawrence M Friedman sekurang-kurangnya harus menyangkut tiga hal, yakni substance (isi atau materi hukum), structure (aparat penegak hukum, dan culture (budaya hukum) (Mahmud MD,2009;106). C. Tipe-Tipe Negara Hukum Seperti diketahui dalam kajian ilmu negara, tipe negara itu dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu sebagai berikut. 1. Peninjauan terhadap tipe negara hukum yang berkembang di dunia dari segi sejarahnya yang sangat panjang sehingga kita dapat mengenal: a. Tipe-tipe negara Timur Purba, yang ciri-cirinya: teokratis, absolut, dan despotis; b. Tipe negara Yunani Kuno, yang ciri-cirinya: polis (City State) dan demokrasi (langsung); c. Tipe negara Romawi Kuno, yang sudah Country State dan despotis/absolut; d. Tipe negara-negara abad menengah, yang ciri-cirinya: dualistis, feodalistis, dan despotis; e. Tipe negara-negara modern, dimulai dari pemikiran Hobbes, Locke dan yang lainnya, yang dapat dibedakan dalam negara hukum yang demokratis dan otokratis.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
442
2. Peninjauan negara hukum dari sisi unsur-unsurnya, hal mana ada pandangan yang menitik beratkan pada unsur wilayah, unsur bangsa/rakyat, atau unsur pemerintahnya. 3. Peninjauan negara hukum dari segi tujuan dan fungsi negara serta hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. D. Latar Belakang Timbulnya Konsepsi Negara Hukum
Istilah rechtstaat (negara hukum) adalah suatu istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah itu pertama kali digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar di Berlin, Jerman, di mana dalam bukunya das Englische Verwaltunngrechte (1875), ia mempergunakan istilah rechtstaat untuk pemerintahan negara Inggris (Fadjar,2005). Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Menurut Asshiddiqie (2009;395) bahwa Plato, pada awalnya dalam the Republic berpendapat bahwa mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosuf (the filosopher king). Golongan pemikir adalah golongan bijaksana (philosopher-king) (Fudyatanta,2006;30). Lebih lanjut terkait hal tersebut, kemudian Plato mengatakan bahwa kebajikan budi dimiliki kaum filsuf, kebajikan keberanian dimiliki oleh militer, sedangkan kebajikan kesederhanaan dimiliki kaum tani dan pedagang-pedagang kecil. Maka untuk itu suatu negara yang ideal seharusnya diperintah oleh kaum filosuf, dipertahankan oleh kaum militer, dan penduduknya harus terdiri atas kaum tani dan pedagang kecil (Gerungan, 2002;5). Namun, secara embrionik gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia menulis Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya, sementara dalam dua tulisan pertama, Politeia dan Politicos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik (Ridwan HR,2011;2).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
443
Senada dengan pendapat Plato tersebut, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (collective wisdom), sehingga untuk itu peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common wealth) (Buadiardjo,2008; 54). Konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad pertengahan di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuasaan absolut dan juga dalam bidang agama yang dipimpin oleh Paus. Hal ini tentunya mengingatkan kita pada teori dua pedang, teori dua pedang sebagaimana dimaksudkan di sini adalah kekuasaan kerokhanian atau keagamaan dan keduniawian. Jadi kekuasaan gereja atau paus merupakan penguasa di bidang keagamaan yang mendapatkan dukungan dari gereja. Sedangkan untuk kekuasaan keduniawian, yaitu kekuasaan negara atau raja. Memang benar selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan Gereja berpuncak pada Paus sebagai kepala Gereja Katolik Roma (Kusumaatmadja dan Agoes,2003:29). Pada mulanya, terlihat bahwa kekuasaan raja dan Paus (gereja) berdempet dalam sebuah wilayah yang sama, yakni yang satu sebagai penguasa politik dan yang lain sebagai penguasa agama (rohani), dengan tuhan sebagai sumber kekuasaannya (Mahmud MD,2010;266). Padahal kedua organisasi kekuasaan tersebut mempunyai subyek yang sama, yaitu manusia dalam satu wilayah. Maka kalau tadi dikatakan bahwa di antara kedua organsiasi kekuasaan itu selalu timbul pertentanganpertentangan, maka terkait dengan pertentangan itu adalah suatu pertentangan mengenai kekuasaan antara negara dengan gereja, terhadap subyeknya. Tegasnya : Siapakah yang mempunyai kekusaan tertinggi di dunia ini terhadap subyeknya, yaitu manusia tadi? (Soehino, 1983;49). Kekuasaan atas warga masyarakat dilakukan oleh gereja dan negara, akan tetapi dalam kenyataannya gereja mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam melakukan peranan penafsir yang sah terhadap hukum tuhan dan hukum alam (Purbacaraka dan Soekanto,1987;29). Selama abad pertengahan, negara kemudian menjadi kurang penting dibanding Gereja, yang bisa memaksakan kekuasaannya pada kekuasaan raja dan memecat para pangeran dan mengatur kebijakan umum (Rodee,2011;7). Beberapa pembela ajaran teokratis adalah sarjana yang pada zaman abad pertengahan sebelum perang salib, dengan ajaran-ajarannya tentang negara dan hukum yang ada, sifatnya adalah sangat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
444
teokratis, seperti Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius di samping banyak sarjana lainnya. Agustinus adalah salah satu sarjana yang membela, bahwa gereja lah yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan raja. Pendapat Agustinus tersebut dengan jelas diterangkan kemudian dalam bukunya De Civitate Dei yang tentunya sebenarnya hanya menggambarkan aliran pikiran yang memang hidup pada masa itu, seperti adanya berbagai pertentangan dan perbedaan tajam pada abad pertengahan di mana ia hidup pada saat itu. Dalam bukunya tersebut Agustinus menyebutkan adanya dua macam negara, yaitu. 1. Civitas Dei, atau Negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Agustinus, karena ini adalah negara yang diangan-angankan, dicita-citakan oleh Agama. 2. Civitas Terrena, atau diaboli, atau Negara Iblis, atau Negara Duniawi ini sangat dikecam dan ditolak oleh Agustinus. Pendapat yang dikemukakan oleh Agustinus tersebut adalah berkaitan dengan kedudukan antara gereja dengan negara, yang menurutnya bahwa kekuasaan geraja merupakan kekuasaan tidak hanya dalam bidang rohani, melainkan juga dalam bidang duniawi. Bahkan, Paus lebih tinggi kedudukannya daripada raja dalam hal memerintah termasuk peraturan-peraturan yang dikeluarkannya. Kemudian, Thomas Aquinas memberikan pendapat yang pada dasarnya masih bersifat teokratis, hanya saja sedikit berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Agustinus terkait dengan kedudukan antara gereja dalam hal Paus dan negara yang diwakili oleh raja. Terkait dengan perimbangan kekuasaan antara gereja dan negara pendapat Thomas Aquinas, bahwa kedudukan atau kekuasaan antara negara dan gereja, yang dikatakan olehnya bahwa organisasi negara yang dipimpin oleh raja mempunyai kedudukan sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh Paus. Hanya saja masing-masing organisasi itu mempunyai tugas yang berlainan, tugas atau kekuasaan negara adalah lapangan keduniawian, sedang tugas atau kekuasaan gereja adalah dalam lapangan kerohanian, keagamaan (Soehino,1983;59). Namun, pada akhirnya perebutan kekuasan antara negara dalam hal ini raja dan gereja dimenangkan oleh raja. Cita-cita itu pada mulanya, sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan yang kuat dari renaissance serta reformasi yang menyertainya. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama Abad Pertengahan telah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
445
disisihkan. Aliran ini membelokan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan Gereja, baik di bidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politik. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya bidang pemerintahan. Ini dinamakan Pemisahan Gerja dengan Negara. Kemudian berlanjut dengan menyelami masa Aufklarung (Abad Pemikiran) beserta rasionalisme, suatu aliran pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh Gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (ratio) semata-mata (Budiardjo,2008;110). Dengan bebasnya manusia dari kungkungan gereja bukan berarti bahwa manusia telah bebas sepenuhnya dari tindakan-tindakan yang menindas. Dikarenakan, sebenarnya ajaran teokratis masih tetap ada, hanya saja berganti kulit. Di mana dulunya kekuasaan Paus dengan legalitasnya dalam bidang kerokhanian yang berdasarkan agama, maka untuk sekarang telah berpindah kepada raja. Raja yang dulunya hanya memegang kekuasaan dalam bidang keduniawian, maka untuk sekarang, ternyata juga mendasarkan kekuasaannya pada ajaran-ajaran yang bersifat teokratis. Kemudian pada dasarnya jika kita cermati secara saksama kembali, maka ajaran teokrasi sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Istilah langsung menunjukan bahwa yang berkuasa dalam negara tersebut adalah langsung Tuhan sendiri. Namun, untuk teokrasi tidak langsung, bukan Tuhan yang memerintah secara langsung, melainkan raja. Raja memerintah atas kehendak Tuhan sebagai karunia (Kusnardi dan Sarigih,2008;64). Bahkan, besarnya kekuasaan berada di tangan raja yang kemudian dengan menyatakan dirinya sebagai wakil tuhan dan tidak bertanggungjawab terhadap kesalahan apapun dan kepada siapapun. Dengan demikian, sebenarnya kekuasaan raja hanya disandarkan pada pengaturan negara berdasarkan kekuasaan yang menurutnya diberikan oleh Tuhan. Apakah sebenarnya yang mendasari keabsahan raja untuk memerintah rakyat? Tanpa bersusah payah persoalan tersebut tadi dijawab oleh teori kuno, bahwa kekuasaan/gezag itu memang karena dikehendaki oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Para dewalah yang menentukan gezag/kekuasaan. Jadi, semua kekuasaan dikembalikan asalnya pada kehendak dewa-dewa. Begitu pulalah kekuasaan Raja Iskandar, dipatuhi/ditaati karena ia dianggap sebagai anak Tuhan Almon (Azhary,1986;13). Menurut teori theokratis soal lahirnya kekuasaan di dalam suatu negara dianggap soal yang mudah, yaitu dianggap hal yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
446
memang sudah menjadi kehendak Tuhan yang gaib oleh karena itu tidak perlu diselidiki lebih mendalam (Dotomuljono,1985;9). Di satu sisi dengan menangnya kekuasaan raja atas gereja telah menentukan kepastian siapakah yang memiliki kekuasaan lebih tinggi antara gereja ataukah raja. Namun, di sisi lain di mana raja telah berhasil memenangkan persaingan terhadap gereja, namun pada dasarnya kedua-duanya tersebut memiliki suatu kesamaan dalam menjalankan pemerintahan, yaitu menindas rakyat. Bahkan, setelah kemenangan raja atas Gereja ternyata dalam menjalankan pemerintahannya menjadi tidak lebih baik, melainkan kemudian bertambah buruk perangainya, terutama terlihat jelas dalam menjalankan kekuasaannya. Adanya peristiwa tersebut, berujung pada rakyatlah yang semakin menjadi sengsara, akibat dari kesewenang-wenangannya bahkan hanya dengan berdasarkan pada kedaulatannya kemudian dijadikan alat legitimasi raja untuk menindas rakyat. Perkembangan kekuasaan raja yang mendapatkan legitimasi dikarenakan adanya ajaran Marsilius. Menurut ajaran Marsilius raja itu adalah wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan dunia. Akibat dari ajaran Marsilius ini maka akhir-akhir abad pertengahan dan pada permulaan zaman berikutnya, yaitu zaman reinaissance, adalah terasa sekali. Karena raja-raja berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya, dengan alasan bahwa perbuatannya itu adalah sudah menjadi kehendak Tuhan. Bahkan, raja merasa berkuasa menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut rakyatnya atau warga negaranya (Soehino, 1986;153). Terkait dengan fenomena seperti itu, dalam kenyataannya rakyat tidak dapat berbuat banyak untuk melawan tindakan penguasa yang sewenang-wenang, karena jika rakyat melawan raja berarti juga melawan kehendak tuhan. Dengan demikian, semua kekuasaan raja yang didasarkan pada dewa-dewa yang memberikan legitimasi, bukan berdasarkan para kehendak rakyat yang diperintahnya. Semua kekuasaan didasarkan atas kehendak dewadewa, meskipun itu tidak dimengerti atau dipahami, tetapi toh harus dipatuhi(Azhary,1986). Raja yang berdaulat itu tidak bertanggungjawab terhadap siapapun kecuali kepada tuhan. Raja adalah legibus solutus. Raja adalah bayangan tuhan. Kedaulatan sebagai Summa in civics ac sabditos legibusque solute potestes, yang berarti kekuasaan supra dari negara atas warga negara dan rakyatnya, yang tidak dibatasi hukum (Huda,2010;170). Selanjutnya dapat dikatakan bahwa berkaitan dengan mutlaknya kekuasaan raja, maka Astawa dan Suprin (2009;112) menyatakan bahwa kekuasaan mutlak yang ada pada raja, sehingga terjadi penyelewenangan kekuasaan ke dalam tirani, seperti halnya Louis XIV di
I Gusti Ngurah Santika, SPd
447
Perancis menyatakan bahwa negara adalah saya (Ietat ces moi). Banyaknya keluarga raja dan para bangsawan yang berpesta pora atas kesengsaraan, menyebabkan rakyat tidak lagi percaya pada kekuasaan tertinggi yang harus berada di tangan raja. Penguasa, dalam hal ini menyamakan dirinya dengan negara. Ucapan ini merupakan ucapan yang sombong, terbit dari keinginan atau keyakinan hendak berkuasa secara mutlak. Yang sebenarnya, pandangan untuk menyamakan negara dengan pemerintah penguasa atau penguasa. Selain minum darah rakyat, para penguasa yang korup itu cenderung menghamburkan uang negara dengan mengadakan pesta-pesta yang mahal (Kumorotomo,2005;2). Semua hal tersebut terjadi tidak lain dikarenakan oleh sistem pemerintahan yang terpusat yaitu hanya kepada satu tangan, yaitu Lous XIV. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, kemudian Tocqueville (2005;65), menyatakan bahwa mustahil kita membayangkan pemerintahan pusat yang lebih lengkap daripada yang pernah ada di Perancis di bawah Louis XIV, ketika dia adalah pembuat dan penafsir hukum, serta merupakan wakil Perancis di dalam dan di luar negeri. LEtat,ces moi (Negara, itulah aku), katanya, dan ia memang benar. Rakyatlah yang pada dasarnya dijadikan objek penguasa bahkan kedudukannya tidak lebih daripada sebagai sapi perah, sedangkan raja sendiri yang karena kedudukannya serta mendapatkan berbagai dukungan dan pembenaran sehingga kemudian dapat menjamin legitimasi, ternyata telah berbuat tidak manusiawi terhadap rakyatnya. Berbagai dukungan berupa pembenaran yang di dapat oleh raja, berkaitan dengan tindakan sewenang-wenangnya terutama oleh para sarjana Eropa lewat berbagai tulisan-tulisan, kemudian berimplikasi semakin membuat raja menjadi-jadi dalam menidas rakyat, tanpa bisa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Doktrin teokratis tulisan sarjana Eropa abad Pertengahan, yang juga bersifat universal disempurnakan, digunakan untuk membenarkan kekuasaan raja-raja yang mutlak. Katakanlah karena raja bertahta karena kehendak tuhan, kekuasaan raja dari tuhan. Dalam teori ini kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada di tangan tuhan. Tuhan dianggap tempat bergantung yang paling utama. Tidak boleh ada yang menganggap apa atau siapa pun yang lebih tinggi kekuasaan dari tuhan. Oleh karena itu, seluruh perintah-perintah negara haruslah merupakan implementasi dari kehendak-kehendak tuhan (Nurtjahjo,2006;31).Bahkan, dalam hal ini memunculkan semboyan Prinsip Legibus Solutus est, Salus Publica Supreme Lex yang artinya rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur daripada negara oleh karena raja adalah satu-satunya pembuat undangundang (Chaidir,2007;24). Bahkan, raja dalam kenyataannya tidak hanya sebagai pembuat undang-undang saja, tetapi raja juga ditentukan memiliki hak untuk melaksanakan undang-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
448
undang ditambah pula dengan melakukan penghukuman terhadap tindakan yang melanggar undang-undang. Pendek kata, dapat dikatakan bahwa raja adalah segalanya pada waktu itu, apa yang dikatakan oleh raja merupakan hukum, jadi jika berani melawan perintah raja berarti menentang hukum negara. Walaupun sebenarnya jelas-jelas tindakan seperti tersebut di atas, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, namun dalam kenyataannya pembenaran terhadap tindakan tersebut datang dari berbagai pihak. Kemudian dalam kenyataannya, seakan-akan raja menutup mata terhadap penderitaan rakyat, serta merasa bahwa tindakannya tersebut sudah merupakan sesuatu yang sangat benar. Nicolo Machiavelli (1469-1627), pemikir Renaissance utama dari Italia dengan bukunya yang terkenal II Le Principe (Buku Pelajaran untuk Raja) telah mengajarkan bahwa tujuan negara yang selalu hendak dituju ialah tercapainya tata tertib dan ketentraman, dan untuk itu hanya mungkin dapat dicapai dengan pemerintahan seorang raja yang kemudian tidak dihalang-halangi dan dirintangi oleh barang sesuatu pun, pemerintahan yang sentralisasi pada raja yang absolut. Terkait dengan bukunya yang berjudul II Principe, dapatlah kemudian diperoleh gambaran jelas mengenai terkenalnya buku ini, menurut Rafar (2002;403) bahwa ketika Henry III dan Henry IV dari Perancis dibunuh, di tangan mereka sedang menggegam buku kecil karya Machiaveli itu : II Principe. Friedrik Agung menerapkan ajaran-ajaran Machiaveli dalam pemerintahannya di Prusia. Louis XIV memilih II Principe sebagai bacaan tetap menjelang tidur. Demikian pula Napoleon Bonaparta, Napoleon III dan Bismarck merupakan murid setia Machiaveli. Adolf Hitler mengatakan bahwa baginya II Principe merupakan sumber inspirasi yang tak ada habis-habisnya. Benito Mussolini pernah mengagumi II Principe dan menjadikannya buku pegangan dalam pemerintahan, kendatipun ia melarang buku itu. Seperti yang terlihat dalam daftar buku terlarang pada tahun 1939. Dalam bukunya II Principe, ia mengajarkan kepada raja-raja bagaimana cara untuk memerintah sebaikbaiknya, bagi Machiaveli seorang raja harus kuat dan tahu cara mengatasi segala kekacauan yang dihadapi negara, ia dapat mempergunakan segala alat yang menguntungkan baginya. Untuk mencapai tujuannya para Raja harus menyelenggarakan pemerintahan tentang real political (Kusnardi dan Sarigih,2008;65). Jika kita telusuri kembali sejarah terkait dengan pembenaran yang diberikan oleh Machiaveli terhadap tindakan raja yang pada dasarnya bersifat sewenang-wenang kepada rakyat. Hal mana adalah tidak terlepas dari sejarah di masa hidupnya Machiaveli, yang kemudian menurut pendapat Kansil dan Cristine (2004;55) bahwa negara Italia pada waktu itu terpecah-belah oleh kekejaman raja-raja yang saling memperebutkan kekuasaan. Negara dianggap hanyalah sebagai suatu organisasi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
449
kekuasaan, memerintah adalah teknik memupuk kekuasaan dan menggerakannya. Machiaveli adalah tokoh yang berusaha meletakan kesatuan politik di Italia daripada sebagai bagian yang terpecah secara politik atau sebagai sarana penampungan keinginan para paus (Rodee,2011;30). Pada waktu itu Machiaveli mencari seorang pangeran yang tahu bagaimana menempatkan persatuan politik di Italia yang terpecah-pecah oleh perpecahan politik dan hak kepausan (Rosyadi,1984;17). Jadi pada dasarnya, Machiaveli yang mempunyai keinginan untuk mempersatukan kembali Italia yang dalam keadaan terpecah belah oleh kekuatan politik, yang memang pada waktu itu kekuatan politik tersebut saling berebut pengaruh untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, Machiaveli tidak menyadari bahwa akibat dari ajarannya tersebut, berjuta orang telah mati dikarenakan penindasan baik yang dilakukan oleh raja di masa lalu, maupun para pemimpin negara yang memang menjadikan ajarannya sebagai pedoman utama untuk memupuk kekuasaan di masa sekarang. Bahkan, dalam mengejar kekuasaan menurutnya, bahwa segala sesuatu yang bersentuhan dengan kebaikan, adalah merupakan awal daripada kehancuran. Untuk itu, Machiaveli berusaha untuk menjauhi segala sifat-sifat baik manusia, yang menurutnya dapat membuat manusia menjadi lemah dan tidak berdaya, terutama dalam mendapatkan kekuasaan. Singkatnya kekuasaan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang sifatnya kotor, karena kemudian kekuasaan yang diperoleh tersebut nantinya akan digunakan kembali untuk melakukan perbuatan kotor pula. Machiaveli menyatakan tidak ada hukum kecuali kekuatan yang dapat memaksakannya. Hanya sesudahnya hak dan hukum akan melegitimasi kekuatan itu. Hukum adalah norma yang diberikan a posteriori oleh penguasa pada luapan atas asal-usul kekuasaan. Asal kekuasaan adalah kekerasan. Dalam politik, kekuatan menentukan, sedangkan moralitas (etika) tidak berdaya (Nurtjahjo,2006;25) Untuk pertama kalinya politik dipisahkan dari moral sehingga terjadi suatu pendekatan yang mekanis terhadap masyarakat. Pengaruh ajaran Machiavelli antara lain suatu ajaran bahwa teori-teori politik dan sosial memusatkan perhatian mekanisme pemerintahan (Astawa dan Suprin,2009;28). Untuk itu, patut kiranya untuk dikutip sebuah contoh yang dapat memberikan gambaran bagaimana jalannya pemerintahan modern, yang dalam kenyataannya tidak ada bedanya dengan ajaran sebelumnya, seperti yang pernah diterapkan oleh Machiaveli pada zaman lampau, kemudian terkait dengan hal tersebut Dahl (2001;64) berpendapat bahwa. Perhatikanlah beberapa contoh dalam abad ke-20. Di bawah pemerintahan Yosep Stalin di Uni soviet (1929-1953), jutaan orang dipenjara karena alasan politik, sering karena penyakit takut (paranoid) terhadap persekongkolan yang akan menentangnya.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
450
Diperkirakan 20 juta orang mati di kamp kerja paksa, dieksekusi karena alasan politik, atau mati karena kelaparan (1932-1933) pada saat Stalin mamaksa para petani ikut serta dalam ladang pertanian yang diurus negara. Meski 20 juta korban lain dari pemerintah Stalin yang bertahan hidup, namun mereka benar-benar menderita. Atau perhatikanlah Adolf Hitler, penguasa otokratis Jerman Nazi (1933-1945). Tanpa menghitung puluhan juta korban militer dan sipil yang diakibatkan oleh Perang Dunia II, Hitler bertanggung jawab langsung atas kematian 6 juta orang Yahudi di kampkamp konsentrasi, sebagaimana juga musuh lainnya yang tidak terhitung seperti orang Polandia, kaum gipsi, kaum homo, serta anggota kelompok-kelompok lain yang ingin dienyahkannya. Di bawah kepemimpinan despotik Pol Pot di Kamboja (1975-1979), Khamer Merah telah membunuh seperempat penduduk Kamboja; dapat dikatakan suatu peristiwa pembunuhan masal (genocide) yang dilakukan sendiri. Pemerintahan seperti dicontohkan tersebut di atas, adalah sesuai dengan konsep daripada Machiaveli yang menurut pendapatnya bahwa perikemanusiaan, moral dan filsafat tidak usah diperhatikan dan harus diabaikan. Raja harus cerdik seperti kancil dan ganas seperti singa. Raja yang hanya memiliki kekuatan saja belum dianggap baik. Raja tak perlu memenuhi janjinya apabila hal itu akan merugikannya. Menurut Machiavelli tujuan negara itu dapat dicapai dengan segala cara, kalau perlu dengan kekerasan, tipuan, dan lain-lain cara yang jahat sekalipun. Inilah prinsip Machiavellisme yang sangat terkenal dan biasa dianut oleh negara-negara totaliter (negara kekuasaan). Tujuan menghalalkan cara atau the End Justifies The Mean (Fadjar,2005;13). Dengan demikian raja akan selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan yang didapatkan walaupun dengan berbagai cara, yang sebenarnya dapat dipandang tidak sesuai dengan sifat seorang raja yang baik. Oleh karena itu pada dasarnya raja-raja ketika itu merupakan penguasa yang kekuasaannya absolut, bahkan kekuasaan raja merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat dalam negaranegara tradisional. Di negara tradisional, sebagian besar penduduk diatur oleh raja atau kaisar yang kebanyakan hanya memiliki sedikit kesadaran atau perhatian terhadap yang diperintahnya (Fatuhrohman dan Sobari,2002;77). Walaupun demikian, dalam kenyataannya tidak banyak rakyat yang mengerti bahkan mengakui terhadap kekuasaan raja tersebut, baik dengan cara berusaha untuk menghindari daripada kekuasaannya. Namun, jika dalam kenyataannya sekali saja bersentuhan dengan kekuasaan raja, maka tidak ada jalan lain lagi selain selanjutnya patuh dan tunduk terhadap perintah yang berdaulat, yaitu raja.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
451
Selain adanya pendapat yang pada dasarnya membenarkan tindakan daripada raja, yang sebenarnya sewenang-wenang oleh Machiaveli. Ternyata juga dari Jean Bodin (15301596) telah pula mengemukakan teori kedaulatan raja dalam bukunya Six Lives de la Republiqus (1576). Dia lah yang kemudian pertama-tama menganggap kedaulatan (sovereinite) sebagai suatu atribut bagi negara, berdasarkan pemikiran tersebut kemudian Jean Bodin membedakan negara dari persekutuan-persekutuan lainnya. Kedaulatan menurutnya adalah bersifat mutlak, utuh atau tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecahpecah serta bersifat tertinggi dalam arti tidak terderivikasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Sebagai akibat daripada hal tersebut di atas maka orang lalu mengenal : (1) interne souveraineteit (kedaulatan ke dalam); (2). Externa souverainiteit (kedaulatan ke luar). Menurut Kansil (2000;167) bahwa penjelmaan Ajaran Machiaveli dengan perumusan yuridis dari Jean Bodin kita dapatkan dalam ucapan raja Louis XIV dari Perancis Leetat cest moi!. Hakikat negara melekat pada kedaulatan, tanpa kedaulatan tidak ada negara. Kedaulatan dipersonifikasi pada raja. Raja yang berdaulat dan tidak bertanggungjawab terhadap siapa pun, kecuali terhadap tuhan. Jadi kedaulatan dan raja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, Thomas Hobbes (1588-1679) menyatakan bahwa manusia selalu hidup dalam kekuatan karena takut akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat keadaan jasmaninya (Busroh,2001;36). Jadi, menurut Hobbes yang menganggap bahwa manusia pada dasarnya adalah saling mencurigai antara satu dengan yang lainya. Kecurigaan tersebut ternyata didasari oleh sifat buruk manusia yang pada dasarnya ingin menghancurkan yang lainnya. Munculnya tulisan Hobbes (1588-1679) yang berjudul The Leviathan, Inti ajarannya diilhami oleh hukum alam fisika, dan matematika. Dia beranggapan bahwa dalam keadaan alamiah, kehidupan manusia didasarkan pada keinginan-keinginan yang mekanis sehingga manusia didasarkan selalu ingin berkelahi. Akan tetapi, mereka mempunyai pikiran bahwa hidup damai dan tentram jauh lebih baik. Keadaan semacam itu baru dapat tercapai apabila mereka mengadakan perjanjian atau kontrak dengan pihak-pihak yang mempunyai wewenang, yaitu pihak yang akan dapat memelihara ketentraman. Supaya keadaan damai tadi terpelihara, orang-orang harus sepenuhnya mematuhi pihak yang mempunyai wewenang tadi. Dalam keadaan demikianlah masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Soekanto,2009;28). Thomas Hobbes dalam menerangkan atau menguraikan ajarannya bertitik tolak pada keadaan manusia sebelum adanya negara (masih dalam keadaan alamiah), di mana manusia itu hidup dalam keadaan alam bebas tanpa abstracto. Dalam kondisi seperti ini manusia
I Gusti Ngurah Santika, SPd
452
selalu saling bermusuhan dan saling menganggap lawan, sehingga selalu timbul peperangan, baik orang melawan seorang lain, ataupun antarkelompok. Keadaan inilah yang disebut dengan Bellum Omnium contra omnes. Situasi Bellum omnium contra omnes disebabkan oleh sifat-sifat manusia. Akibatnya terjadilah penindasan di antara yang satu dengan yang lainnya (Kaelan,2010;61). Bagi Hobbes keadaan alamiah sama sekali bukan suatu keadaan yang aman dan sejahtera, tetapi sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar-individu di dalamnya (ICCE UIN,2010;87). Dalam keadaan semacam ini yang berlaku adalah hukum kepalan (vuistrecht) artinya siapa yang kuat dia yang menang dan berkuasa, karena setiap orang itu hidup menurut hukumnya sendiri-sendiri (Kusnardi dan Sarigih,2008;65). Dengan demikian, menurut pendapat Hobbes bahwa satu-satunya cara untuk mengelakan suasana perang tersebut harus ada penguasa (souvereign) yang dapat mengatur dan mengendalikan konflik dalam masyarakat manusia (Amien Rais,1989;26). Berdasarkan paparan tersebut di atas, ternyata Hobbes sama sekali telah melupakan sifat baik daripada manusia, yang sebenarnya dibawa sejak lahir sebagai kodratnya seorang manusia, seperti adanya sifat sosial. Karena menurut Hobbes bahwa belas kasih, katanya, merupakan imajinasi atau fiksi dari bencana di masa datang yang menimpa kita, yang muncul dari kesadaran akan bencana yang dialami orang lain (Rachels,2008;128). Dalam kesadaran manusia tersebut, takut adalah faktor alasan manusia yang paling kuat, maka oleh karenanya takut itu mencambuk manusia untuk membentuk negara dan gezeg. Manusia tidak aman dalam alam liar, di sana manusia yang satu untuk yang lain seperti binatang ganas yang berbahaya, homo homini lupus (Kranenburg,1983;16). Dengan begitu, tinjauan Hobbes terhadap sifat manusia, adalah suatu tinjauan yang hanya disimpulkan dari sifat-sifat buruk manusia saja. Bahkan, kemudian dia menyamakan kedudukan manusia dengan hewan, sehingga bagi Hobbes tiada bedanya antara sifat manusia dengan hewan, yang pada dasarnya berkeinginan untuk saling berkelahi dengan tujuan agar dapat memenangkan persaingan tersebut, yang berarti dapat mengalahkan manusia lainnya untuk mampu mempertahankan kehidupannya. Manusia dalam status naturalis dianggap oleh Hobbes seperti binatang buas terhadap yang lainnya. Untuk menghilangkan rasa takut manusia satu dengan manusia lainnya, untuk membuat agar binatang-binatang buas itu tidak membahayakan yang lainnya, maka perlu diikat, dibatasi, dibatasi kebuasaannya. Dan dengan tujuan tersebut mereka membentuk suatu organ/perjanjian masyarakat, dibentuklah badan tadi, yang tidak lain adalah negara (Azhary,1986;17). Dengan demikian, diperlukan satu kekuasaan yang berpusat, sehingga kemudian dapat mengendalikan manusia-manusia yang pada dasarnya berkeinginan untuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
453
saling menghancurkan satu sama lainnya. Terus bagaimanakah caranya agar manusiamanusia tersebut tidak lagi saling meniadakan antara yang satu dengan yang lain, agar terciptanya kedamaian? Menurut Hobbes agar perdamaian kemudian dapat terselenggara dengan baik maka diperlukan suatu perjanjian. Berdasarkan pendapat Hobbes tersebut, kemudian Astawa dan Suprin (2009;76) menyatakan bahwa manusia kemudian mengadakan perjanjian, yang selanjutnya disebut dengan perjanjian masyarakat untuk membentuk negara. Tujuannya adalah agar manusia dalam negara yang diperjanjikan tersebut dapat bekerja untuk memiliki sesuatu dan tidak terancam jiwanya. Setelah diadakan perjanjian masyarakat di mana individu-individu menyerahkan haknya atau hak-hak asasinya kepada suatu koletivitas yaitu kesatuan dari individu-individu yang diperolehnya melalui pactum unions, maka di sini kolektivitas menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja dalam paktum subjetiones tanpa syarat apapun juga. Kemudian setelah terkumpulnya hak-hak rakyat tersebut, dan diserahkan kepada seseorang penguasa untuk menyelenggarakan hakhak rakyat. Hak-hak rakyat itulah yang memberi dasar kepada penguasa yang memegang hak-hak rakyat tersebut. Seorang penguasa yang mahakuasa mengumpulkan segala kekuasaan negara dalam dirinya (Sutikno,2008;38). Kemudian dalam kenyataannya raja sama sekali ada di luar perjanjian, dan oleh karenanya raja mempunyai kekuasaan yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya (Monarchie Absolut), itulah gambaran tidak hanya dari Hobbes tetapi juga dari Machiaveli. Hobbes mendukung bahwa raja harus memiliki kekuasaan mutlak atas rakyatnya (Hardiman,2007;73). Hal mana adalah sangat sesuai dengan pikiran mereka saat itu, kedua pemikir tersebut juga cenderung memilih monarki, mereka percaya bahwa suatu monarki yang kuat adalah pemerintahan yang paling mantap dan yang paling mungkin menjamin stabilitas (Rodee,2011;31). Sudah jelaslah kemudian bahwa semua hal yang baik dalam kehidupan, baik yang bersifat material (kebendaan) maupun spiritual (kerohanian), pertama-tama dan terutama tergantung pada keamanan kehidupan itu sendiri. Sebab jika tidak ada kekuasaan untuk memaksakan kehendak yang berdaulat, maka tidak ada pemerintahan, tidak ada negara, tidak ada keamanan (Rosyadi,1984;17). Untuk itu, maka kekuasaan harus diserahkan hanya kepada satu orang, sebagai pemegang kekuasaan dalam bentuk monarki. Monarki yang dimaksud oleh Machiaveli dan Hobbes adalah monarki absolut, yang tidak adanya pembatasan terhadap raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam negara. Karena belum adanya batas-batas yang jelas sampai dimana kekuasaan seorang raja, dengan demikian berakibat pula terhadap hak-hak semula yang sebelumnya telah diserahkan kepada raja sehingga akan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
454
terancam oleh penyalahgunaan oleh raja, yang pada akhirnya akan menindas pemilik hak tersebut. Tidak lain pikiran yang mendasari hal tersebut adalah raja dalam kenyataannya tidak dapat disalahkan dalam segala tindakannya walaupun nyata-nyata telah melanggar hak-hak asasi manusia, bahkan tindakan raja itu adalah legal apabila tujuannya adalah menjamin manusia yang satu tidak saling meniadakan dengan manusia yang lainnya, yang sesuai dengan perjanjian manusia ada awalnya membentuk negara. Kenyataan tersebut adalah sesuai dengan pendapat dari Hutauruk (1978;25), yang menyatakan bahwa guna mencegah kehancuran jenisnya, maka manusia itu mengadakan perjanjian satu sama lain untuk tidak membunuh, untuk mengakhiri struggle of the fittest, lalu membentuk suatu negara dan pemerintahan yang berkuasa penuh. Kepada pimpinannya diserahkan manusia itu secara mutlak semua hak dan kemerdekaannya. Diterimanya kembali keamanan dan ketentraman. Dengan jalan demikian lahirlah kekuasaan absolutisme negara itu. Di dalam perjanjian itu (ini perjanjian masyarakat Hobbes) tersimpul penyerahan dari individu-individu kepada masyarakat kecuali dari raja bahwa raja di sini tidak ikut dalam perjanjian. Demikian menurut Thomas Hobbes, karena raja bukan partai dalam perjanjian itu, maka raja tidak ada janji-janji apalagi terikat oleh perjanjian, maka kekuasaan raja adalah absolut. Raja dapat melaksanakan apa saja, bahkan diperbolehkan membunuh sekalipun, asal ini untuk perdamaian yang menjadi tujuan daripada perjanjian masyarakat, jadi untuk mencapai tujuan negara. Kalau raja berbuat melawan hukum, tidak dapat dikatakan raja itu bersalah, atau melanggar hak orang lain, atau melanggar perjanjian masyarakat itu sendiri, sebab raja tidak bertanggungjawab kepada siapa-siapa. Palingpaling hanya dianggap bahwa raja itu berdosa terhadap tuhan, tetapi terhadap negara atau masyarakat atau rakyat atau individu tidak. Karena raja itu berada di luar partai-partai atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Inilah yang merupakan alasan yuridis bagi kekuasaan raja yang absolut itu (Soehino,1983;101). Agar kekuasaan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban itu bisa dilaksanakan dengan baik, atau agar kekuasaan itu dipatuhi oleh masyarakat dengan baik, atau agar kekuasaan itu dipatuhi oleh masyarakat maka dianggap perlu untuk memberikan kekuasaan yang tanpa dibatasi. Karena jika orangorang hendak menentukan batas-batas kekuasaan tersebut, mungkin penentuan batas-batas tersebut dapat menimbulkan suatu pertikaian, dan pertikaian menimbulkan rasa takut. Lagi pula kekuasaan yang tanpa batas dianggap perlu untuk membatasi kekuasaan lain yang ada di bawahnya untuk bisa menguasai keamanan dan ketertiban (Azhary,1986;18). Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya berkaitan mengapa kekuasaan penguasa tidak perlu dibatasi, dinyatakan bahwa apabila ,gezag pemerintah diberikan batas, maka terdapat kemungkinan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
455
perselisihan mengenai batas itu, jadinya menghidupkan kembali takut dan untuk mengelakan yang belakangan ini dulu telah dijadikan alasan pembuatan perjanjian. Dalam pokoknya kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan melakukan ibadah tidak dapat diakui, oleh karena pengakuan itu mengandung kemungkinan diterimanya hak memerintah orang lain daripada oleh pemerintah dan dengan demikian kemungkinan pertikaian dan timbulnya kembali takut. Tujuan utama perjanjian pembentukan negara hilang, apabila terhadap ancaman hukuman pemerintah ditaruh ancaman-ancaman hukuman akhirat, Hobbes telah mengalami sendiri mengganasnya secara hebat perang-perang agama (Kranenburg,1983;17). Ada berbagai alasan yang kemudian menyebabkan kekuasaan mutlak diberikan kepada raja. Salah satunya seperti apa yang selanjutnya dikemukakan oleh Huda (2011;42), menurutnya bahwa . Sang daulat tak mungkin melanggar perjanjian, karena ia tidak mengikat perjanjian itu, jadinya ia tidak melepaskan hak-haknya. Karena itu ia tak mungkin bertindak tidak adil terhadap rakyatnya. Memang ia dapat bertindak tidak sepatutnya, tetapi ia tidak mungkin bertindak berlawanan dengan hukum. Jadi rakyatnya pun tak dapat menuduh bahwa ia telah berbuat demikian atau telah melanggar perjanjian, selebihnya rakyat juga tak dapat menyatakan kehendak mereka untuk melakukan perlawanan. Kedaulatan ialah kekuasaan tanpa batas untuk kepentingan tujuan-tujuan negara. Berbeda dengan Hobbes, menurut John Locke antara raja dengan rakyat diadakan perjanjian dan karena itu raja (negara) yang berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyat. Kalau raja (negara) bertindak sewenang-wenang, rakyat dapat minta pertanggung jawabnya, karena yang primer adalah hak asasi yang dapat dilindungi oleh raja, maka timbul monarchie constitusionil atau monarki terbatas, karena kekuasaan raja (negara) sekarang menjadi terbatas oleh konstitusi. Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat dari Soemantri (1992;1) yang menyatakan bahwa teori tentang perjanjian ini terbagi menjadi dua, yaitu masih mengakui adanya hak warga negara, karena dalam perjanjian itu yang diserahkan bukan seluruh milik individu. Hal ini berbeda dengan perjanjian kedua, yang beranggapan bahwa seluruh milik individu dalam perjanjian itu diserahkan kepada organisasi yang bernama negara. Oleh karena itu teori perjanjian pertama telah menghasilkan bentuk negara yang demokrasi, sedangkan untuk teori perjanjian yang kedua menghasilkan bentuk negara yang totaliter. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa teori perjanjian yang diterapkan oleh Locke merupakan teori yang nantinya akan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
456
menghasilkan bentuk negara yang sifatnya demokratis. Menurut Locke (1632-1704) bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. John Locke sendiri mendasarkan teorinya pada keadaan manusia dalam alam bebas. Dan memang menganggap bahwa keadaan alam bebas atau keadaan alamiah itu mendahului adanya negara, dan dalam keadaan itupun telah ada perdamaian dan akal pikiran seperti halnya dalam negara. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Thomas Hobbes, karena Thomas Hobbes mengatakan bahwa keadaan alamiah itu tidak ada aturan, tidak ada perdamaian. Jadi keadaannya lain sekali dengan keadaan negara (Soehino,1983;107). Jadi, Locke melihat bahwa manusia pada dasarnya telah memiliki hak-hak yang dibawa sebelum hidup bernegara, maka tujuan diadakan perjanjian adalah menjamin hak-hak yang dimiliki sebelum mereka bernegara. Karena dalam mengadakan perjanjian dengan seseorang atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Menurut Locke, masyarakat terdiri dari warga negara dan raja yang membentuk sebuah alat pemerintahan bersama untuk menginterpretasi dan melaksanakan hak-hak umat manusia yang sudah ada sejak semula sebelum kondisi politik itu ditetapkan (Strong,2005;47). Ada hak-hak alamiah yang merupakan hak asasi yang tidak dapat dilepaskan, juga tidak oleh individu itu sendiri. John Locke (1932-1704) yang menganut paham status naturalis dimana manusia dalam keadaan zaman purba telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan, kemudian faham status civilis di mana rakyat sebagai warga negara dilindungi oleh negara tentang hakhak dasar pribadinya, yang menimbulkan aliran liberalisme dengan staatsonthouding nya (Adji,1978). Dengan demikian, pada dasar hakhak yang tidak diberikan kepada raja merupakan suatu hak asasi, dan juga merupakan hak yang terkuat yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun termasuk raja itu sendiri. Hal ini membuka timbulnya ajaran tentang hak-hak dasar manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa inti ajaran John Locke adalah pembatasan-pembatasan kekuasaan negara, demi perlindungan kepentingan individu (Astawa dan Suprin,2009). Bahkan, menurut Locke hak rakyat tidak ada bedanya dengan penguasa, karena raja berkuasa atas kehendak rakyat lewat perjanjian yang di dalamnya telah ditentukan hak-hak rakyat yang tidak berbeda dengan raja. Hal ini didasari tanpa suatu persamaan fundamental akan status, maka peranan sosial dari individu yakni suatu bentuk peranan sosial tidak mempunyai dasar (Viller dan Siedentop,1986;94). Dalam pada itu, penguasa yang diserahi tugas mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraaan harus menghormati hak-hak asasi itu. Untuk itu, tugas-tugas penguasa yang akan dilakukan terutama menyangkut masalah hak asasi manusia harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Menurut Locke bahwa pemerintahan dengan persetujuan diartikan bahwa tidak ada bidang kekuasaan yang fungsinya dilakukan oleh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
457
pemerintahan bertentangan dengan kehendak rakyat ataupun kehendak wakil-wakilnya (Sasronegoro,1984;52). Kemudian Fadjar (2005;17) berpendapat dengan menyatakan bahwa dalam konstruksi demikian, Locke menghasilkan negara yang dalam kekuasaannya dibatasi oleh hak-hak kodrat yang tidak dapat dilepaskan itu. Maka, ajaran Locke menghasilkan negara konstitusional, bukan negara absolut. Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara yang hak-hak dasarnya kemudian dilindungi oleh negara (Sihombing,2009;28). Sebab dalam kenyataannya Locke menilai bahwa kekuasaan tertinggi merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat (Junaidi,2010;45). Jadi, semenjak itu mulailah legitimasi raja bergeser bahkan menurun di hadapan rakyat, dikarenakan telah timbul pula kesadaran rakyat akan kekuatan mereka, seraya mulai menyadari bahwa sebenarnya kekuasaan pada raja merupakan kehendak rakyat sendiri. Oleh karena itu, menurut Renan (1994;24-25) berpendapat bahwa asas kuno, yang hanya mementingkan hak-hak raja-raja, tidak mungkin dipertahankan lagi, selain dari hak dinastik adalah juga hak kebangsaan (nasional). Doktrin umum ini mudah diterapkan oleh Locke untuk keadaan istimewa pada tahun 1688 dan sudah masuk dalam resolusi Konvensi tahun 1689 yang menurunkan Raja James II dari tahta. Resolusi ini menegaskan bahwa raja telah melakukan segala daya upaya untuk menumbangkan konstitusi kerajaan dengan melanggar perjanjian semula antara raja dan rakyattelah menurunkan tahta pemerintahan dan dengan demikian, tahta kerajaan dinyatakan kosong. Demikianlah, ketika James II setelah tiga tahun pemerintahannya yang buruk telah diturunkan dari tahta, agaknya telah dibuat perjanjian baru untuk menobatkan William of Orange dan Putri Mary di atas tahta kerajaan Inggris (Strong,2005;47). Maka untuk selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan yaitu diperlukan suatu pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia tersebut. Kemudian dengan adanya pembagian kekuasaan, atau membagi kekuasan raja, tentunya terkait dengan jaminan hak asasi manusia akan diperoleh kemudian. Bahkan, dalam bukunya Two Treaties on Civil Government John Locke telah menyarankan untuk selanjutnya membagi kekuasaan dalam tiga badan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif (disebutnya federatif power of the commonwealth), yang masing-masing terpisah yang satu dari yang lain. Kekuasaan legislatif meliputi membuat peraturan, kekuasaan eksekutif meliputi mempertahankan peraturan serta mengadili perkara (Locke melihat mengadili sebagai uitvoering) dan kekuasaan federatif meliputi segala sesuatu yang tidak termasuk lapangan yang kedua kekuasaan yang disebut pertama itu (Utrecht,1986;16).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
458
Kemudian ajaran pembagian kekuasaan untuk membatasi kekuasaan raja dari Locke menghilhami Chales Secondat Baron de Labrade et de Montesquieu atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Montesquieu (1688-1755) merupakan seorang pemikir besar yang membuat karya yang sangat terkenal, yaitu I Espirit des Lois(The Spirit of Law), Jiwa Undang-Undang (Fadjar,2005). Untuk itu, maka keluarlah teorinya yang sangat dikenal dengan nama Trias Politika, yang pada dasarnya memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang kekuasaan. Cabang kekuasaan sebagaimana dimaksudkan di atas adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif yang pada dasarnya terpisah satu sama lain, baik mengenai organ maupun fungsinya. Selanjutnya, yang juga ikut ambil bagian dalam usaha revolusi Perancis adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dengan fahamnya yang sangat terkenal, yaitu kedaulatan rakyat. Paham Rousseau adalah kebalikan daripada Hobbes. Menurut Hobbes paactum unions ditelan oleh pactum subjektiones sedang Rousseau pactum subjektiones yang ditelan oleh pactum uniones. Oleh karena itu, akibat daripada ajaran Rousseau adalah kedaulatan rakyat tidak pernah diserahkan pada raja bahkan kalau ada raja yang memerintah maka raja itu hanya sebagai mandataris daripada rakyat (Kusnardi dan Sarigih,2008;77). J.J Roesseau mengemukakan bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah di dalam paham demokrasi ini adalah melalui perjanjian masyarakat (social contract) yang berkonsekuensi bahwa jika dalam menjalankan tugasnya pemerintah itu bertindak secara bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka pemerintah itu dapat dinauzlkan (dijatuhkan) oleh rakyatnya (Mahmud MD,2001;67). Sebagai sarjana yang membatasi kekuasaan raja (penguasa), menentang absolutisme, ialah sarjana-sarjana penganut aliran hukum alam dan motor utama hukum alam. Ia juga mendasarkan teorinya pada perjanjian masyarakat, bahkan dia lah yang pertama-tama menggunakan istilah kontrak sosial dalam bukunya Contract Social yang ditulis tahun 1762. Menurut Rousseau, keadaan alamiah (status naturalis) tidak bisa terus dipertahankan maka diakhiri dengan kontrak sosial, keadaaan alamiah beralih ke keadaan bernegara (status civilis). Manusia dilahirkan merdeka, namun di mana-mana ia terbelenggu (man is born free and everywhere he is inchains) (Fadjar,2005). Namun bagi Rosseau, manusia terlahir bebas dan masyarakat sipil adalah suatu kebutuhan, serta persetujuan (consent) adalah satu-satunya dasar yang absah bagi kekuasaan politik (Wahab dan Sapria,2011;276). Pemerintah sebagai pimpinan organisasi dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat, yaitu rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya (volonte generale). Dengan perjanjian masyarakat itu, berarti tiap-tiap orang yang melepaskan dan menyerahkan semua haknya kepada kesatuannya, yaitu
I Gusti Ngurah Santika, SPd
459
masyarakat. Kemudian rakyat menyerahkan hak-hak mereka kepada pemerintah untuk dijaga bukan disalahgunakan seperti dahulunya. Pemerintah hanyalah dianggap sebagai wakil daripada rakyat yang memegang kedaulatan rakyat. Mereka yang melaksanakan tugas pemerintahan hanyalah melakukan tugasnya atas nama rakyat (Azhary,1983;19). Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Kontrak sosial menentukan disatu pihak bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana di mana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (natural right) dengan aman. Dipihak lain rakyat akan menaati pemerintahan raja asal hakhak alam itu terjamin (Budiardjo, 2008;111). Ajaran Rosseau yang mempertahankan bahwa kedaulatan itu tidak bisa lepas dari rakyat (onvervreemd-baar) dalam praktik tidak benar dengan adanya kekuasaan yang diwakilkan. Dalam ajarannya yang penting adalah bahwa kedaulatan itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan kehendak, sehingga kedaulatan rakyat diwujudkan dalam pernyataan rakyat untuk menyampaikan kehendaknya. Dari gagasan atau ajarannya tersebut dapat dipahami bahwa hal yang terpenting dalam konsep pemikiran tentang negara dan hukum Rosseau adalah ihwal kedaulatan rakyat (Ridwan dan Sodik,2010;190). Dalam ajarannya yang penting adalah bahwa kedaulatan itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan kehendak, sehingga kedaulatan rakyat diwujudkan dalam pernyataan rakyat untuk menyampaikan kehendaknya. Kehendak rakyat itu disampaikan melalui dua cara, yaitu: 1. Kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan volonte de tous. 2. Kehendak sebagian besar rakyat yang dinamakan volonte generale. Menuru Rosseau, Volonte de tous hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya sekali saja, ketika negara hendak dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Maksud volonte de tous ini memberi dasar agar negara dapat berdiri abadi, karena ini merupakan kebulatan kehendak. Jika negara itu sudah berdiri, pernyataan setuju tidak bisa ditarik kembali (Astawa dan Suprin,2009;81). Maka, setelah itu volonte de tous tidak dipergunakan lagi dalam menjalankan pemerintahan, hal ini disebabkan jika selalu dilakukan dengan suara bulat, maka jalannya roda pemerintahan sudah di pastikan tidak dapat dilakukan. Maka sebagai kelanjutannya, yang merupakan kelanjutannya volonte de tous, volonte generale dinyatakan setelah negara berdiri, yaitu dengan suara terbanyak. Cara demikian ini yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
460
lazim dipergunakan dalam negara-negara demokrasi liberal. Jadi, kedaulatan yang dimaksud oleh Rosseau sama dengan keputusan suara terbanyak atau diktaktor suara terbanyak (meeder-heids dictatuur). Bahkan, orang Romawi menciptakan istilah vox populi, vox dei suara rakyat adalah suara tuhan. Machiavelli menulis dalam Discoursi, Bukannya tanpa alasan bahwa suara rakyat dibandingkan dengan suara Tuhan, dan dia berpendapat bahwa rakyat harus diperhatikan atau dimusnahkan (Cutlip,dkk,2006;100). Dengan teori ini, dasar kekuasaan negara itu bukan lagi vox dei (suara Tuhan) akan tetapi vox populi (suara rakyat), meskipun kerap kali keduanya disetarakan atau yang satu dinisbahkan ke yang lain melalui ungkapan vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Inilah dasar legitimasi yang baru (menggantikan teori kedaulatan Tuhan) bagi kekuasaan pemerintah (Mahmud MD,2010;268). Teori kedaulatan rakyat ini juga diikuti oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas perundang-undangan, sedangkan undangundang di sini yang berhak membuat adalah rakyat sendiri. Maka kalau begitu undangundang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan (Soehino,1983;161). Selain itu, masih ada lagi satu ajaran yang sekarang sangat popular, yaitu ajaran kedaulatan hukum merupakan ajaran paling modern yang dikemukakan oleh Krabbe, menurut Kusnardi dan Sarigih (2008;127) bahwa kekuasaan tertinggi itu tidak terletak pada kehendak pribadi daripada raja, melainkan terletak pada hukum yang tidak berpribadi (on personnlijk). Ajaran ini tertulis dalam karangannya yang berjudul Dier Lehre derrechts souveraneit. Yang dimaksud oleh Krabbe sebagai sumber hukum adalah yang terpenting, yang datang dari kesadaran hukum daripada manusia itu sendiri yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan menentukan baik tidaknya suatu peraturan hukum yang berlaku serta diterima oleh rakyat. Menurut Astawa dan Suprin (2009) bahwa penguasa negara hanya memberikan perumusan formal saja kepada hukum yang telah ada dalam diri setiap manusia. Bahkan, penguasa pun berasal dari hukum dan harus mengapresiasi hukum, harus tunduk kepada hukum serta menegakan hukum yang telah dibuat berdasarkan hati nurani. Menurut Krabbe dalam Aveldoorn (2011;439) bahwa hukum berpangkal pada perasaan hukum dan hanya memperoleh kekuasaan dari persesuaiannya dengan perasaan hukum individu. Ia mengajarkan : bagi saya hanyalah merupakan kaidah, apa yang berpangkal pada perasaan hukum saya, karena kaidah itu memerintah saya, menguasai kehendak saya. Menurut Krabbe hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formal diundangkan oleh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
461
badan legislatif sesuatu negara. Hukum (dan kedaulatan sebagai aspeknya) bersumberkan perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan hukum adalah sumber dan merupakan pencipta hukum, negara hanya memberi bentuk pada perasaan hukum itu. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan pencipta hukum, negara hanya memberi bentuk pada perasaan hukum itu. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum. Negara tidak berdaulat mutlak, karena perasaan hukum menentukan dan membatasi isi hukum. Bukan negara tetapi hukumlah yang berdaulat (Fadjar,2005;16). Namun, pernyataan ini kemudian mendapatkan kritik dari Aveldoorn (2011;439) yang menyatakan bahwa kemudian di sini timbul sesuatu kesukaran yang besar. Sesuatu kaidah hukum, yang berpangkal pada perasaan hukum individu hanya menguasai kehendak individu itu sendiri, jadi adalah hukum hanya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi hukum, sebagai kaidah dari masyarakat, harus menguasai seluruh anggota masyarakat, jadi bersandar kepada keyakinan hukum bersama. Sedangkan Dotomuljono (1985;11) berkaitan dengan teori kedaulatan hukum, menyimpulkan bahwa suatu tindakan alat-alat perlengkapan Negara (pemerintah harus melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Kedaulatan hukum memandang bahwa kekuasaan itu bersumber dari aturan hukum (supremasi hukum). Ia tidak setuju dengan pendapat bahwa negara dapat memaksakan kehendaknya terhadap rakyat. Bukankah dalam kenyataannya bahwa rakyat tunduk pada peraturan negara tidaklah karena kehendak alamiah atau paksaan negara, melainkan karena memerlukan akan adanya tata tertib hidup jadi kesadaran hukum rakyatlah yang membuat mereka tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuat negara. Dari kenyataan sejarah dapat kita lihat bahwa negara itu sendiri tunduk pada hukum, dan negara juga bertanggung jawab atas perbuatan onrechtmatige dari alatalat perlengkapannya. Di samping itu kadangkala kita melihat negara tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk menghentikan pertumbuhan, perkembangan hukum baik secara biasa maupun secara revolusioner (Azhary,1986;22). Dalam tipe negara hukum ini, hukumlah yang berdaulat, negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara salah, maka ia dapat dituntut dimuka pengadilan sebagaimana halnya dengan subjek hukum yang lain (manusia) (Kansil dan Christine,2002;165) Demikianlah konsepsi negara hukum (rechtstaat) itu dilahirkan pada abad ke-17 dan 18, melalui tulisan-tulisan para sarjana penganut aliran hukum alam. Sebagai reaksi dan tantangan terhadap absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya, kekuasaan penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat dan warganya. Di negara-negara Eropa
I Gusti Ngurah Santika, SPd
462
Kontinental, konsep negara hukum tersebut, selanjutnya, dikembangkan oleh Immanuel Kant, Friederich Julius Stahl, Fichte, Laband, Buys, dan lain-lainnya, yang terkenal dengan istilah konsep Rechtstaat sedangkan,di negara-negara Anglo Saxon lahirlah konsep semacam, yang terkenal dengan konsep Rule of Law, yang dipelopori oleh Dicey (Fadjar, 2005;20). Kemudian dua orang sarjana Barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan Friederich Julis Stahl telah mengemukakan buah pikiran mereka. Kant memahami negara hukum sebagai Nachtwakertstaat atau Nachwachterstaat (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum liberal. Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu: 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 2. Negara didasarkan pada teori trias politika; 3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur); 4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) (Tahir Azhary,2010;89, Kusnardi dan Sarigih,2008;93, Mahmud MD dan Marbun,2000;44). Di negara-negara Anglo Saxon berkembang pula suatu konsep negara hukum yang semula dipelopori oleh A.V.Dicey (dari Inggris) dengan sebutan rule of law. Konsep ini menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama,yaitu. 1. Supremasi aturan-aturan hukum (Supremacy of law), tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. 2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equlity before the law), di mana dalil ini berlaku baik untuk orang, selaku pejabat maupun bukan pejabat. 3. Terjaminnya hak asasi manusia berdasarkan konstitusi(the constitution based on the individual rights) (Saidi,2007;27, Kusnardi dan Sarigih,2008;93, Tutik,2008;72, Asshiddiqie,2009;199).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
463
Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring perkembangan masyarakat dan negara. Professor Utrecht dalam Asshiddiqie (2009) membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formal atau negara hukum klasik, dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undangundang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip laiesez faire laiesize aller. Yang artinya biarlah setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya jangan negara ikut campur tangan. Dalam bidang hukum dan kenegaraan aliran ini berpendapat bahwa negara harus bersifat pasif, ia hanya mengawasi dan bertindak apabila terjadi perselisihan antara anggota masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingannya (Kusnardi dan Sarigih,2008;132). Dalam prinsip negara hukum formal negara hanya mengurusi urusan umum, sedangkan berkaitan dengan kepentingan private negara tidak ikut campur, bahkan kepentingan pribadi merupakan hal yang primer. Ini merupakan konsep daripada negara liberal yang mengutamakan kepentingan individu di atas segala-galanya. Bahkan, Baldwin (2007;293) mengungkapkan dengan kata-kata seperti apa gunanya? Aku tidak peduli, tidak perlu, adalah ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan. Menurut Moeljatno (2008;9-10) bahwa hal mana adalah sesuai pula dengan pandangan individual liberal, di mana pada pokoknya diajarkan, bahwa tiap orang adalah bebas dalam mengatur hidupnya menuju kepada kebahagiaannya sendiri. Namun, dapat saja terjadi seperti apa yang dinyatakan oleh Soepomo (1983;5) bahwa individu itu selalu hendak menonjolkan diri sebagai aku. Dia adalah suatu pusat kekuasaan. Dia selalu berusaha memperbesar kekuasaannya. Maka di dunia terjadilah dari individu-individu yang terdiri sendiri-sendiri berhadap-hadapan satu sama lain, senantiasa mengadu tenaga dalam perebutan kekuasaan. Memang pada bahwa esensinya individualisme adalah ajaran bahwa di dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah individu. Segala interaksi dalam masyarakat harus dilakukan demi kepentingan individu (Kumorotomo,2005;30). Seperti negara-negara barat yang sangat mengutamakan kemampuan seseorang sehingga mampu bertahan untuk hidup tanpa bantuan orang lain, dapatlah dicontohkan dalam hal ini adalah Amerika. Masyarakat Amerika menghargai setiap orang yang berusaha sendiri jadi bila seseorang memulai dari nol dan mencapai standar hidup yang tinggi, tak seorangpun akan mengeluh (Lerner,1983;196). Mereka puas dengan falsafah biarlah masing-masing mengatur dirinya sendiri dan terserah kepada
I Gusti Ngurah Santika, SPd
464
masing-masing untuk menentukan spesifikasi yang eksak dari tujuan akhir yang dikejarnya (Suriasumantri,2009;110). Bolehlah kemudian terkait hal tersebut dikatakan bahwa berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (homo homini lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain(Santoso dan Zulfa,2010;3). Bahkan menurut Profesor Utrecht (1986;19) tentang negara hukum formal yang menyatakan bahwa negara hanya mempunyai tugas primer untuk melindungi dan menjamin kedudukan ekonomi dari golongan penguasa (ruling class) dan bisa disebut negara jaga malam. Semboyan liberalisme abad ke -19, yang selalu di kutip dalam bahasa Perancis, berbunyi: laisessez faire, laissezp asser. Artinya: biar saja, jangan campur tangan. Tetapi gaya kebebasan liberalisme ini pada kenyataannya berarti penindasan bagi banyak orang (Bertens,2011;110). Hal ini dikarenakan bahwa dalam negara kapitalis berkepentingan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan kelas dominan, yaitu pemilik kapital. Hal yang sebenarnya menurut teori ini adalah suatu kerja sama antara yang mengontrol negara dan mereka yang memiliki dan mengontrol alat-alat ekonomi. Negara memang memiliki identitas sendiri dan mampu bertindak secara independen dalam memelihara dan mempertahankan tata sosial. Namun kelas ekonomi dominan itulah yang akhirnya menerima manfaat terbesar (Bungin,2008;32). Couwenberg seperti yang dikutip Latif (2009;87-88) dalam bukunya Wester staatrecht als Emancipatie procces, mengemukakan prinsip-prinsip dasar yang sifatnya liberal dari rechtstaat, mencakup sepuluh bidang, yaitu adanya; 1. Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (de scheiding tussen staat en burgelijke maatschappij), pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan, pemisahan antara hukum publik dan hukum privat; 2. Pemisahan antara negara dan gereja (agama); 3. Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (Bugerlijke vrijheids rechten); 4. Persamaaan terhadap undang-undang (gelijkheid voor de wet); 5. Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum; 6. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem checks and balances;
I Gusti Ngurah Santika, SPd
465
7. Asas legalitas (heerschappij van de wet); 8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral; 9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan bebas dan tidak memihak; 10. Prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi) Menurut Zainuddin dalam Dahl (1992;xxxiv;) yang menyatakan bahwa liberalisme memiliki tujuan ganda, yaitu pengendalian yang rasional terhadap pemerintahan melalui demokrasi dan pengendalian rasional terhadap soal-soal ekonomi akan sangat diperkuat dengan menjadikan masalah-masalah ekonomi itu merupakan permasalahan pemerintahan. Tetapi peranannya tersebut terbatas kepada menyediakan dan mengembangkan infrastruktur dan menjalankan administrasi pemerintahan (Sukirno,2010;394). Alasan jelas, yaitu bahwa soal-soal yang berkenaan dengan perkonomian tidaklah menyangkut urusan kenegaraan, melainkan termasuk ke dalam wilayah urusan pasar yang mempunyai mekanismenya sendiri sesuai dengan prinsip free market liberalism yang dianggap sebagai pilar penting dalam sistem kapitalisme (Asshiddiqie,2009;163). Dalam sistem liberalisme dengan konsep perekonomian pasar bebas menerangkan bahwa pemerintah memang mempunyai peranan yang cukup penting dalam kehidupan perkonomian suatu negara. Namun, Adam Smith berpendapat bahwa campur tangan pemerintah yang aktif dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi akan semakin mengurangi efisiensi kegiatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan dalil yang menjadi aliran pemikiran liberalisme yaitu pemerintahan yang paling sedikit adalah yang paling baik (the least government is the best government), atau dengan istilah staatsounthouding. Negara dalam pandangan ini dianggap sebagai Negara Penjaga Malam (nachtwachterstaat) yang sangat sempit ruang geraknya, tidak hanya bidang politik, tetapi terutama di bidang ekonomi (Budiardjo,2008;114). Bahkan, lebih dari dua abad yang lalu Adam Smith menyatakan bahwa kegiatan perkonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah, karena dengan konsep invisible hand atau tangan gaib dengan sendirinya perekonomian akan berhasil. Menurut Adam Smith apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diingini mereka, maka kebebasan ini akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara dan jangka panjang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
466
kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan yang teguh (Sukirno,2010;394). Hanya saja kelemahan ini mengabaikan kemampuan dari tiap-tiap individu yang kemampuan dan sumber daya manusia yang dimilikinya maupun sumber daya yang lainnya. Oleh karena itu, individu yang kemampuan dan sumber dayanya kurang akan selalu kalah dalam persaingan. Hal itu tidak dapat diatasi oleh mekanisme pasar, sehingga memerlukan intervensi pemerintah (the visible hand). Di samping itu, sistem ekonomi kapitalis liberal mempunyai penyakit bawaan, yaitu krisis ekonomi. Akibatnya kondisi ekonomi selalu digoyang kongjungtur yang makin tajam (Rindjin,2009;256). Iiberalisme dan individualisme yang dijadikan dasarnya ternyata hanya menguntungkan kaum borjuis atau mereka yang kuat secara ekonomis, sedangkan mereka yang secara ekonomis lemah (golongan miskin) selalu menjadi golongan yang dirugikan karena dalam memperjuangkan keinginan-keinginannya mereka tidak mempunyai fasilitas, sehingga selalu kalah dalam persaingan bebas itu (Mahmud MD dan Marbun,2000;45). Dapat dipastikan bahwa hanya individu yang mampu bersaing yang akan dapat berbicara(Saud,2011;90). Dengan demikian, maka tidak adanya kemampuan yang sama di bidang kehidupan ekonomi mengakibatkan adanya ketergantungan dari seseorang atau sekelompok orang kepada pihak yang kedudukan ekonominya kuat. Asas kemerdekaan dan persamaan terutama di bidang ekonomi menyebabkan terjadinya persaingan yang bebas. Setiap orang bebas untuk melaksanakan dan mencapai tujuan-tujuannya. Meskipun terdapat asas persamaan, akan tetapi oleh karena tersebut tidak disertai dengan kemampun yang sama, akhirnya yang akan berhasil dalam persaingan itu adalah mereka yang berkedudukan kuat, terutama sekali yang menguasai bidang kehidupan lainnya, seperti umpamanya bidang politik. Sebagai akibatnya timbullah dalam masyarakat dua golongan, yaitu golongan the haves dan golongan the haves not(Soemantri,1992;16-17). Pelaksanaan laissez-faire selama periode ini menyebabkan kesengsaraan hebat. Pada akhirnya, munculnya konsepsi baru tentang fungsi ekonomi suatu negara menumbuhkan keyakinan bahwa pemerintah harus lebih banyak ambil bagian dalam mengatur kesejahteraan ekonomi masyarakat (Strong,2005;447). Dengan demikian dapat dinyatakan tentang kesimpulan daripada faham liberalisme bahwa. Faham politik yang telah mencoba mewujudkan cita-cita kemerdekaan ke dalam kehidupan sosial ialah liberalisme. Faham liberal ialah intisari program-progam, yang pada akhir abad ke-18 menarik dengan serempak kekuasaan-kekuasaan yang paling berpengaruh di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Konstitusi Amerika Serikat, Revolusi Perancis dan awal industrialisasi modern Inggris kemudian memberi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
467
dorongan yang dasyat pada faham itu. bertujuan menyusun negara dan kehidupan ekonomi berdasarkan kemerdekaan perseorangan(Soemantri,1992;13). Semenjak akhir abad ke 19 telah timbul pandangan yang mengkritik keyakinan tersebut. Kritik dan kesadaran tentang kelemahan-kelemahan sistem pasar bebas telah mendorong pemerintah untuk lebih banyak campur tangan dalam kegiatan ekonomi (Sukirno,2010;395). Konsepsi dan praktek legal state atau negara hukum yang lama ternyata telah menimbulkan kepincangan sosial (Mahmud MD dan Marbun,2000;45). Oleh karena itu, tidak bisa pemerintah menyerahkan segala-galanya kepada mereka. Pemerintah harus mengambil inisiatif, memimpin dan mengontrol (Widjaja dan Swasana,1983). Kemunculan daripada sistem liberal yang menurut Arief (2010;17) sebenarnya sejak zaman renaissance ajaran-ajaran filosofisnya menonjolkan paham individualisme, liberalisme, dan hakhak individu. Namun, setidaknya aliran tersebut telah menyebabkan banyak orang yang menderita akibat ketidak pedulian daripada pemerintah terhadap nasib rakyat. Sedangkan dilain pihak kaum kapital telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya, yang tentunya kemudian tidak mudah untuk dihadapi, sekalipun itu oleh negara. Oleh karena itulah, selanjutnya banyak negara yang meninggalkan konsep liberalisme secara murni, walaupun tidak semuanya benar-benar ditinggalkan. Kemudian berjalan untuk melompat ke sistem negara kesejahteraan, terutama untuk meratakan kesejahteraan rakyat dengan ikut campur tangannya pemerintah terhadap urusan-urusan rakyat, yang dulunya tidak dicampur tangani oleh pemerintah. Sejarah menunjukan bahwa rechtstaat telah mengalami perkembangan dari konsep klasik ke konsep modern. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik disebut klassiek liberale en democratische rechstaat yang sering disingkat dan dipopulerkan dengan sebutan democratische rechstaat. Sedangkan konsep modern lazimnya disebut sociale rechtstaat atau disebut socialedemocratische rechtstaat (Latif,2009;87). Adapun ciri-ciri negara kesejahteraan (welfare state) adalah sebagai berikut. 1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbanganpertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ-organ legislatif. 2. Peranan negara tidak hanya terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban belaka, akan tetapi negara secara aktif berperanan di dalam penyelenggaraan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
468
kepentingan-kepentingan masyarakat di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga perencanaan merupakan sarana yang sangat penting. 3. Negara kesejahteraan merupakan negara hukum materil yang mementingkan keadilan sosial materiil dan bukan persamaan yang bersifat formal semata-mata. 4. Sebagai konsekuensi dari hal-hal tersebut di atas, maka di dalam suatu negara kesejateraan hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi hak tersebut dipandang mempunyai fungsi sosial yang berarti adanya batas-batas di dalam kebebasan penggunaannya. 5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara di dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Ini adalah sesuai dengan fungsi negara modern (Soekanto, 2008;313-314). Negara hukum dalam arti materiil (luas modern) ialah negara yang terkenal dengan istilah welfare state (wolvaar staat), (welfare staat), yang menjaga keamanan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (social security) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hakhak warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi. Menurut Muchsan (1981;2) bahwa dalam teori negara kesejahteraan, untuk dapat mencapai tujuannya (kesejahteraan bagi masyarakat), negara dituntut untuk mencampuri segala aspek kehidupan masyarakat, mengurusi semua sejak manusia itu lahir sampai mati (from the crad leto the grave). Tidak satupun aspek kehidupan masyarakat yang terlepas dari campur tangan negara. Bahkan, hanya dengan campur tangan tersebutlah hak-hak rakyat dapat terselenggara, terutama berkaitan dengan hak rakyat untuk menikmati kesejahteraan. Kemudian berkembang ada hak dasar manusia (basic right) dan ada hak asasi manusia (human right) (Sunaryo,2009;24). Oleh karena itu, International Comission of jurists pada konferensinya di Bangkok, memberikan ciri-ciri rule of law/negara hukum yaitu. 1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individual konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
I Gusti Ngurah Santika, SPd
469
3. Pemilihan umum yang bebas; 4. Kebebasan menyatakan pendapat; 5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; 6. Pendidikan kewarganegaraan(Sunarno,2009;26,Nurtjahjo,2006;43, Mahmud MD dan Marbun,2000;46, Mahmud MD,2010;181). Dari pencirian seperti itu terlihat bahwa adanya pengakuan terhadap perluasan tugas pemerintah (eksekutif) agar menjadi lebih aktif tidak hanya selaku penjaga malam. Pemerintahan diberi tugas dan tanggung jawab membangun kesejahteraan dan pemerataan yang adil bagi rakyatnya. Ciri-ciri negara hukum di atas sudah dipengaruhi oleh konsepsi hukum materiil (modern) (Winarno,2009;121). Gagasan bahwa pemerintah dilarang ikut campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang ekonomi (staatsounthouding dan laissez faire) lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejateraan rakyat dan kerenanya harus ikut mengatur kehidupan ekonomi sosial (Budiardjo,2008;115). Hal mana adalah sangat sesuai dengan tujuan negara, bahwa pada esensinya negara bertujuan untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan rakyat (welvaart staat, welfare state) seperti apa yang kemudian di amanatkan oleh konstitusi. Dengan ini, kemudian ditinggalkan pula pandangan kuno, yang pada dasarnya waktu itu memandang negara semacam jaga malam atau nachtwaker dalam arti, bahwa negara dengan alatalat perlengkapannya hanya bertugas untuk menjaga agar para anggota masyarakat dalam hidupnya sehari-hari tidak bertengkar, dan agar, hubungan ini diatur secara tertib (Prodjodikoro,1981;15). E. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Negara untuk dapat dinyatakan sebagai suatu negara hukum. Sebenarnya tidak tergantung apakah disebut dalam undang-undang dasar atau tidak, walaupun di dalam undang-undang dasar ada ditentukan bahwa negara hukum, belum tentu menjamin apakah negara itu dalam praktek yang sebenarnya adalah negara hukum. Yang kemudian menjadi paling penting apakah prinsip-prinsip negara hukum dilaksanakan atau tidak (Sotomo,1983;7). Ternyata hanya dengan adanya konstitusi belum kemudian dapat menjamin bahwa negara tersebut merupakan negara hukum, yang tentunya hanya mungkin dapat diketahui kembali dari adanya praktek-praktek ketatanegaraan, apakah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal mana adalah sesuai sekali dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
470
pendapat, Kelsen (2011;373) yang menyatakan bahwa monarki absolut pun mempunyai konstitusi, sebab setiap negara memiliki konstitusi di sini memberi kekuasaan yang hampir tidak terbatas kepada raja untuk menerbitkan tidak hanya norma-norma umum, tetapi norma-norma khusus dan untuk menjalankan tindakan-tindakan paksa, sehingga setiap tindakan raja atau organ yang diberi kekuasaan olehnya tampak sebagai tindakan negara, jika tindakan ini menampakan dirinya sendiri demikian. Jadi, kesimpulannya bahwa negara hukum bukanlah hanya berada di atas kertas, melainkan negara yang memang benar-benar dalam kenyataannya mempraktekan prinsip-prinsip negara hukum. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu: 1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law); 2. Persamaan dalam hukum (Equality Before of the Law); 3. Asas Legalitas (Due process of Law); 4. Pembatasan Kekuasaan; 5. Organ-Organ Penunjang yang Independen; 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; 7. Peradilan Tata Usaha Negara; 8. Mahkamah Konsitusi (constitutional court); 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat); 11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat); 12. Transparansi dan Kontrol Sosial (Asshiddiqie,2009;397). Sedangkan menurut Azhary (2010;105-153) merinci prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut. 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah; 2. Prinsip musyawarah;
I Gusti Ngurah Santika, SPd
471
3. Prinsip keadilan; 4. Prinsip persamaan; 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 6. Prinsip peradilan bebas; 7. Prinsip perdamaian; 8. Prinsip kesejahteraan; 9. Prinsip ketaatan rakyat. Kemudian Fadjar (2003;43) mengemukakan tujuh prinsip negara hukum, yang menurutnya mutlak bagi sebuah negara untuk disebut sebagai negara hukum. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip negara hukum menurutnya, yaitu. 1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; 2. Asas legalitas; 3. Asas pembagian kekuasaan negara; 4. Asas peradilan bebas dan tidak memihak; 5. Asas kedaulatan rakyat; 6. Asas demokrasi; dan 7. Asas konstitusional. Prinsip-prinsip negara hukum menurut J.B.J.M Ten Berge (dalam Ridwan HR,2011;9) yaitu. 1. Asas Legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal);
I Gusti Ngurah Santika, SPd
472
2. Perlindungan hak asasi manusia; 3. Pemerintah terikat pada hukum; 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus ditegakan, ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah; 5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Dengan adanya prinsip-prinsip negara hukum tersebut di atas , merupakan suatu ukuran yang kemudian dapat menjadi penilai tentang negara untuk selanjutnya menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Sehingga dengan demikian setiap orang tidak mungkin dapat memberikan pendapatnya dengan sebebas-bebasnya tentang negara hukum, tanpa didasari oleh adanya prinsip-prinsip sebagaimana maksudkan di atas. Dikarenakan bahwa prinsip-prinsip di atas merupakan bingkai, yang diharapkan akan menjadi tolok ukur untuk memberikan penilaian apakah negara tersebut adalah layak untuk disebut sebagai negara hukum. Berkaitan dengan prinsip negara hukum, tidak tertutup kemungkinan selain apa yang telah disebutkan oleh para ahli terkait dengan prinsip-prinsip negara hukum di atas, ternyata ada prinsip-prinsip negara hukum yang lainnya. Untuk itu, diperlukan ahli-ahli yang memang konsen terhadap perkembangan negara hukum, sehingga dapat menemukan lagi prinsip-prinsip yang lainnya. F. Negara Hukum Indonesia Terkait dengan negara hukum Indonesia, memang sebelum Perubahan UndangUndang Dasar 1945 ketentuan mengenai negara hukum tidak dinyatakan secara tegas (eksplisit), hal mana dapat kemudian dilihat pada Batang Tubuh UUD 1945, yangdi dalamnya berisi pasal-pasal. Kenyataan tersebut dapatlah kemudian dimaklumi merupakan suatu kealpaan oleh pendiri negara (the founding people). Salah satu alasan yang mungkin dapat diberikan, yaitu dikarenakan situasi dan kondisi pada saat penyusunan UUD 1945, yang memang pada kenyataannya tidak memberikan waktu lebih panjang lagi dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
473
penyusunan UUD 1945, sehingga masih banyak hal yang belum dapat diperdebatkan, untuk kemudian hasilnya dimasukan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Namun, menyusul kemudian dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan tidak terbatas); tanpa adanya penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan negara hukum (rechtsstaat). Dengan adanya Penjelasan UUD 1945 tersebut, walaupun mungkin kehadirannya menyusul setelah UUD 1945 ditetapkan, ternyata dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai konsep negara hukum, yang dikehendaki oleh para pendiri negara untuk Indonesia nantinya. Pada dasarnya Penjelasan UUD 1945 terkait dengan sistem pemerintahan negara, telah memberikan penjelasan historis bahwa mengenai negara hukum, bukanlah barang baru bagi bangsa Indonesia. Karena memang sebelum UUD 1945 ditetapkan, berkaitan dengan negara hukum sebenarnya sudah menjadi perdebatan hangat antara anggota BPUPKI, yang memiliki tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, kemudian berlanjut kembali pada sidang-sidang PPKI. Dan sampai akhirnya dengan disahkannya UUD 1945, terkait dengan konsep negara hukum yang dinginkan oleh para pendiri negara, adalah apa yang secara jelas dicantumkan di dalamnya. Selain adanya pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus. Ternyata pengertian negara hukum sebagaimana dalam Penjelasan UUD 1945, seperti dimaksud di atas, adalah lebih mencerminkan konsep negara hukum formal, yang pada dasarnya hanya mendasarkan hukum semata. Namun, jika kemudian dilihat kembali pada bagian lain dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, maka dapat ditemukan kembali pada bagian II Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan dari Penjelasan UUD 1945 tersebut, maka dapatlah kemudian dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil. Dengan demikian, pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum, yang tidak hanya berdasarkan konsep negara hukum formal melainkan juga sebagai negara hukum yang bersifat materiil, dimana kesemuanya dapat ditemui dalam UUD 1945, khsususnya dalam Penjelasannya, yang masing-masing letaknya terpisah satu sama lainnya. Kemudian terkait dengan negara hukum materiil yang dianut Indonesia, maka dapatlah kemudian dibaca pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yaitu.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
474
1. Negara - begitu bunyinya - melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur (kursif penulis). Dengan demikian, dalam kenyataannya sebelum Penjelasan UUD 1945 dihapus pada dasarnya Indonesia adalah suatu negara hukum, bahkan tidak hanya dalam pengertian negara hukum formal, melainkan sekaligus juga negara hukum dalam arti materiil. Bahkan, negara hukum Indonesia tidak melepaskan sendi kedaulatan rakyat sebagai dasarnya, yang juga dengan meletakan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai rahmat-Nya, bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang kekal dan abadi. Untuk lebih mengerti dan memahami apa yang kemudian dimaksud dengan negara hukum, kiranya tidak cukup apabila kemudian hanya dijelaskan kembali dengan beberapa kalmia,t seperti yang ada di dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus sebagaimana dimaksud di atas. Maka berdasarkan pemaparan tersebut, sebelum memasuki pembahasan terkait dengan negara hukum Indonesia, Rahardjo (2009;81-82) kemudian memberikan pendapat terkait dengan cara membahas negara hukum Indonesia, yaitu sebagai berikut.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
475
Sebelum membahas negara hukum Indonesia, maka terlebih dahulu membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai jantung dan jiwa negara. Undang-undang dasar suatu negara memberi tahu kepada kita tentang apa yang dimaksud pembentuk negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang yang ingin dilakukannya, serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya dengan undang-undang dasar, suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju yang dicita-citakan. Undang-undang dasar juga sangat penting bagi penyelenggaraaan hukum suatu negara, oleh karena itu pada saat-saat tertentu hukum perlu melihat panduan yang diberikan oleh undang-undang dasarnya. Hal tersebut terjadi, misalnya, pada saat hukum mengalami kebuntuan dan tidak tahu ke mana harus melangkah. Jadi, pendapat yang kemudian disampaikan menurut Sadjipto Rahardjo, berkaitan dengan konstitusilah/undang-undang dasar yang perlu dijadikan sebagai kajian dalam meneliti apakah negara tersebut memang benar-benar merupakan negara hukum atau bukan. Pendapat tersebut dapatlah dimengerti, dikarenakan undang-undang dasar sendiri berkedudukan sebagai hukum dasar, di samping sebagai acuan bagi penyelenggaraan bernegara, yang kemudian diimplementasikan kembali dalam praktek kehidupan bernegara. UUD 1945 di dalamnya terdapat prinsip-prinsip negara hukum, dengan tujuan utamanya adalah menjamin rakyat sendiri sebagai pemegang kedaulatan, selanjutnya mampu memberikan batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Dengan menempatkan undang-undang dasar sebagai aturan dasar, tentunya jika di dalam undang-undang dasar sendiri tidak adanya jaminan, bahwa negara tersebut menganut negara hukum, maka sudah dapat dipastikan selanjutnya bahwa negara tersebut akan terjerumus atau tergelencir ke dalam negara kekuasaan, hal mana paling tidak hanya menunggu waktu saja, untuk kemudian masuk ke dalam sistem pemerintahan yang sifatnya otoritarianisme. Tentu saja pada gilirannya, akan menyebabkan kedudukan hukum yang sudah seharusnya supreme/superior terhadap kekuasaan, terlihat menjadi lemah bahkan tidak berdaya jika keduanya berhadapan secara langsung satu sama lainnya. Sehingga kedaulatan rakyat sebagai konsep utama yang tercermin dalam hak asasi dan pembatasan kekuasaan pemerintahan, selanjutnya perlu mendapatkan jaminan dalam konstitusi, tidak lain dikarenakan dapat dijadikan sebagai dasar serta acuan daripada interaksi diantara kedua konsep tersebut. Untuk itu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, hendaknya mendapatkan kesempatan pula untuk ikut terlibat membentuk aturan dasar, yang dalam kenyataannya benar-benar dapat memberikan jaminan, bahwa hukumlah yang kemudian menjadi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
476
panglima, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa bisa kembali ditafsirkan secara politik, bahkan dijalankan oleh penguasa dengan tangan besinya. Selain itu, menurut Asshiddiqie (2002;56) negara hukum memerlukan suatu jaminan yang tentunya harus berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat). Dengan demikian maka, seharusnya hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam undang-undang dasar. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (constitusional democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (Democratische rechtsstaat). Dengan demikian, hukum harus membatasi semua tindakan yang dilakukan oleh siapapun, rakyat sebagai pemegang kekuasaan sendiri dalam negara demokrasi saja perlu dibatasi oleh hukum, apalagi kekuasaan yang hanya dipegang oleh satu orang penguasa. Tentunya jika rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tidak dibatasi oleh hukum, maka yang timbul bukanlah negara hukum dalam arti yang sebenarnya melainkan menjadi negara anarki, yang tentunya dalam hal ini berpotensi akan memunculkan seorang yang tirani, dikarenakan tidak ada aturan yang jelas dalam membatasi tindakan penguasa untuk mengatur demokrasi yang sudah menjadi anarki. Tirani inilah yang kemudian berusaha untuk mengatur rakyat, yang pada dasarnya telah menjadikan kedaulatannya sendiri menjadi anarki, kemudian dengan perlahan-lahan tapi pasti mencoba untuk mengkonsolidaskan kekuasaannya lalu menjadikan dirinya sebagai diktaktor, sehingga pada akhirnya menindas semua orang. Dengan demikian, konsep demokrasi belum tentu dapat mewujudkan negara hukum, namun perlulah diketahui bahwa negara demokrasi harus berdasarkan hukum, yang kemudian menjelma menjadi negara hukum yang demokratis. Maka menurut rumus daripada democratiche rechtsstaat, maka demokrasi itu sendiri adalah merupakan staatssvorm, sedangkan rechtsstaat asas negara hukum yang membatasi demokrasi agar tidak menjadi anarki. Maka atas dasar itulah rumusan negara kita sebaiknya menganut democratiche rechtsstaat(Mahkamah Konstitusi,2010;420 ).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
477
Indonesia pun sejak awal berdirinya berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai suatu negara hukum yang betul-betul demokratis. Sehingga dalam negara hukum yang demokratis, tentunya akan meletakan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama, dalam posisi paling tinggi yang kemudian tercantum dengan jelas dalam konstitusi, seperti Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian, negara Indonesia telah menjamin bahwa adanya kedaulatan rakyat sekaligus juga ditentukan dan dibatasi oleh hukum tertinggi, baik dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang pada dasarnya merupakan perintah langsung untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang ada di dalam UUD 1945. Sebelum adanya perubahan terhadap UUD 1945 memang terkait dengan konsep negara hukum sebagaimana dimaksudkan di atas belum tercantum dengan jelas. Menyadari masalah tersebut, dimana selama hampir 50 tahun, negara Indonesia telah menjalani negara hukum yang bersifat formal semata. Karena dengan hanya mendasarkan diri pada hukum semata, padahal kemudian hukum yang dibuat tersebut, telah melanggar prinsip-prinsip negara hukum materiil. Tidak lain, dikarenakan hukum yang dibuat oleh penguasa ternyata didasari oleh undang-undang dasar yang sifatnya kurang demokratis. Kurang demokratisnya UUD 1945, telah pula menimbulkan efek negatif dalam usaha mencapai negara hukum materiil. Karena terlihat kemudian dari hukum yang didasari oleh UUD 1945 sebelum amandemen, ternyata jika ditafsirkan kembali satu pasal dapat mengeluarkan dua peraturan yang maknanya berbeda, terutama berkaitan dengan tingkat demokratisnya daripada hukum terlahir kemudian. Namun, jika lihat kembali dalam UUD 1945 sebelum diadakan perubahan, ternyata titik berat pencapain daripada negara hukum, bukanlah terletak pada aturan dasar, yang seharusnya memberikan pedoman dalam menyelenggarakan negara. Melainkan dalam hal ini, UUD 1945 telah menyerahkan dirinya lewat pengaturan lebih lanjut kepada semangat para penyelenggara negara, untuk mencapai negara hukum yang bagaimana diharapkan kemudian. Tentunya semua pencapaian negara hukum, akan sangat tergantung pada semangat penyelenggara negara nantinya. Hal mana dapat diketahui dengan melihat kembali dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, yang di sana dengan tegas menjelaskan bahwa. Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lainlain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum
I Gusti Ngurah Santika, SPd
478
dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut. Demikianlah sistem UndangUndang Dasar. Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin supel (elastic) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang (verouderd). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang (kursif penulis). Ternyata, dengan adanya keterangan yang telah diperoleh dari Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, maka dapatlah diketahui kemudian mengapa dalam sejarah perjalanannya selama ini negara hukum Indonesia yang memang dicita-citakan ternyata tidak kunjung tercapai. Tidak lain, konsep negara hukum yang dimaksudkan dalam Penjelasan 1945 di atas tersebut, ternyata semua pengaturan sangat tergantung pada semangat penguasa yang ditugaskan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, terkait dengan adanya penyerahan pada semangat penyelenggara negara dalam mencapai negara hukum, Mahmud MD (2011;378-379) kemudian berpendapat bahwa pernyataan tersebut benar untuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
479
sebagian, tetapi kurang benar untuk seluruhnya. Dikarenakan, jika saja semangat para penyelenggara negara itu baik, namun apabila pengaturan sistem ketatanegaraannya kurang baik, maka negara cenderung menjadi kurang baik, sebab kekuasaan pada dasarnya adalah cenderung korup. Hal ini adalah sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Lord Acton dalam Budiardjo (2008;107) yang menyatakan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (Power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely). Terbukti dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang dalam kenyataannya hanya dengan mengandalkan semangat para penyelenggara negara, ternyata tidak mampu untuk menghadapi godaan buruk akan kekuasaan. Sebagaimana dinyatakan para ahli sebelumnya tersebut, berkaitan dengan kecendrungan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, dalam kenyataannya juga terjadi di Indonesia. Dikarenakan selama ini, berkaitan dengan kata kekuasaan memiliki arti yang tidak terbatas, terutama bagimana cara mengendalikan luasnya kekuasaan, namun hanya dengan mengandalkan kemampuan manusia yang sifatnya terbatas, yaitu berupa semangatnya saja. Dengan demikian, selama ini negara hukum hanya menjadi gincugincu ketatanegaraan, di samping hanya hidup dalam tataran teori yang tentunya masih sangat jauh dari realitas (kenyataan), sebagaimana yang dicita-citakan. Dikatakan seperti tersebut di atas, dikarenakan jika kita mengetahui kisah di masa berlakunya UUD 1945, diawali ketika disahkannya UUD 1945 tersebut sampai dengan 19 Oktober 1999, di mana pada waktu itu dimulainya perubahan pertama terhadap UUD 1945. Sehingga, untuk mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hanya mungkin dapat dicapai kemudian dengan melakukan demokratisasi terhadap UUD 1945, khususnya perubahan yang dilakukan adalah terhadap pasal-pasalnya. Dengan demikian, diperlukan perubahan terhadap UUD 1945, yang sebenar menjadi hukum dasar dalam kehidupan bernegara. Peristiwa tersebut merupakan hal penting dalam menuju negara demokratis yang berdasarkan hukum yang diberkati oleh konsep Ketuhanan Yang Maha Esa guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta mampu meletakan dasar yang jelas terhadap konsep negara hukum sebagai wujud implementasi daripada kedaulatan rakyat, maka UUD 1945 sebagai sumber utama untuk mencapai cita-cita, telah dilakukan amandemen, sehingga diharapkan benar-benar sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis. Menurut Rahardjo (2009;2) bahwa dari amandemen-amandemen dibuktikan secara jelas, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tidak statis, melainkan memiliki dinamika. Amandemen keempat tersebut dapat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
480
dibaca sebagai keinginan bangsa Indonesia untuk lebih mempertegas identitas negaranya sebagai suatu negara hukum. Apalagi sistem UUD 1945 kemudian dilekati dengan paham dan asas demokrasi, konstitusi, negara berdasarkan atas hukum, dan berbagai paham negara kesejahteraan (Kosmas,2009;48). Beberapa konsep yang berkaitan dengan negara hukum kemudian dimasukan ke dalam UUD 1945, tentunya konsep negara hukum tersebut, tidak hanya menganut ajaran formal saja, melainkan diharapkan juga mengandung konsep negara hukum material. Dengan demkian, akan terdapat suatu keseimbangan antara konsep negara hukum formal dengan negara hukum material, tanpa terjadi saling meniadakan satu sama lain, melainkan saling mendukung untuk berusaha mencapai kedua-duanya secara bersamaan. Sebenarnya lebih tepat jika dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang unsur-unsurnya terdiri dari : 1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara; 2. Adanya pembagian kekuasaan; 3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis; 4. Adanya kekuasaan kehakiman merdeka(Soemantri,1992;49) yang dalam menjalankan kekuasaannya
Negara hukum Pancasila merupakan konsep tengah yang ditawarkan agar dapat tercapai keseimbangan terutama dalam mencari unsur-unsur negara hukum dari berbagai konsep negara hukum yang telah ada. Dengan demikian, politik hukum kita tentang konsepsi negara hukum yang menganut unsur-unsur, baik dari rechtsstaat maupun rule of law, bahkan kedua sistem hukum tersebut sekaligus. Di mana sebelumnya, konsep negara hukum Indonesia ditegaskan di dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, dengan kalimat Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), untuk sekarang Penjelasan UUD 1945 sudah tidak berlaku karena sudah dihapus. Namun, pernyataan prinsip negara hukum itu penuangannya di dalam konstitusi dipindahkan ke dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan kalimat netral, yaitu, Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara lebih jelas dapat dikemukakan bahwa penghilangan istilah rechtstaat dari UUD tersebut bukanlah masalah semantik atau Gramatik semata melainkan juga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
481
menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatik. Sebab, seperti diketahui ada dua istilah yang berbeda yaitu rechtstaat dan the rule of law (Rol). Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam satu istilah yang sama, yaitu negara hukum padahal kedua istilah (rechtstaat dan Rol mempunyai kosepsi dan pelembagaan secara berbeda (Mahmud MD,2009;95). Perbedaan itu dilatar belakangi konsep rechtstaat yang lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari sisi atau kriteria rechstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechtstaat berdasar atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sedangkan konsep the rule of law berdasar atas sistem hukum yang disebut common law (Latif,2009;86). Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan penguasa. Kekuasaan yang menonjol dari rechtstaat ialah membuat peraturan atau undang-undang berdasarkan asas legalitas, dengan prinsip bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap sah sampai adanya suatu keputusan yang menyatakan ketidakabsahannya itu. Sebaliknya, kekuasaan utama dari the rule of law adalah memutus sengketa dari peradilan yang bebas dan adil berdasarkan hukum yang lahir dari masyarakat. Dengan pendapat yang sama, Mahmud MD (2009;95) menyatakan bahwa istilah rechtstaat adalah istilah untuk negara hukum yang dipakai di negara-negara kawasan Eropa Kontinental yang lebih menekankan pada pentingnya hukum tertulis (civil law) dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam rechtstaat lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal; artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Titik berat penegakan hukum di dalam rechtstaat adalah kepastian hukum sehingga hakim yang baik adalah hakim yang dalam membuat putusan dapat menerapkan dan menemukan hukumhukum tertulis yang pasti. Di dalam rechtstaat hakim merupakan corong UU. Sedangkan the rule of law (Rol) adalah istilah untuk negara hukum di negara-negara kawasan Anglo Saxon yang lebih menekankan pada pentingnya hukum tak tertulis (common law) demi tegaknya keadilan substansial. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam Rol lebih berpijak atau menegakan tegaknya substansi keadilan daripada kebenaran formal-prosedural semata; artinya yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis melainkan bisa yang tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat; dan karenanya hukum tertulis (UU) dapat disimpangi oleh hakim jika UU itu dirasa tidak adil. Karena titik berat Rol adalah keadilan maka dalam membuat putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilainilai keadilan di dalam masyarakat. Dasar hukum buatan-hakim (jugde-made law) dibangun dengan kekuatan preseden; artinya, keputusan hakim terdahulu biasanya dianggap
I Gusti Ngurah Santika, SPd
482
sama mengikat dengan keputusan hakim sesudahnya untuk kasus-kasus yang sama, meskipun variasi keputusan itu berkembang seiring dengan waktu dan keputusan terdahulu itu sebagai pedoman (Strong,2005). Dengan demikian, maka menurut Mertokusomo (2005;4) bahwa: putusan pengadilan itu tidak hanya mengikat mereka yang berpekara atau terhukum saja akan tetapi mengikat juga pengadilan-pengadilan lainnya, terutama pengadilan yang lebih rendah, dalam arti bahwa dalam memutus perkara sejenis, pengadilan tidak boleh menyimpang dari pengadilan putusan atasannya. Jika sesuatu peraturan dalam keputusan hakim selalu diikuti, dengan perkataan lain, jika mengenai sesuatu pertanyaan hukum yang tertentu, telah terbentuk yurisprudensi yang bersifat tetap, maka peraturan tersebut dapat merupakan hukum obyektif, bukan berdasar atas putusan hakim, melainkan berdasar atas kebiasaan, yakni berdasarkan kesadaran hukum umum, yang menjelma dalam garis-garis tingkah laku para hakim (Apeldoorn,2011;161-162). Semua itu kemudian tercermin dalam putusan-putusan pengadilan yang harus diperhatikan oleh hakim-hakim dalam memutuskan perkara-perkara baru kemudian (Prodjodikoro,1986;5). Tidak berbeda jauh dengan pernyataan di atas, Han Kelsen (2011;2014) menyatakan bahwa keputusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Keputusan pengadilan bisa memiliki kekuatan pengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang di tanganinya saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa lain yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Keputusan pengadilan bisa memiliki karakter yurisprudensi, yakni sebagai keputusan yang mengikat bagi keputusan mendatang dari semua kasus yang sama. Jadi yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama (Kansil dan Christine,2002;22). Lebih lanjut menurutnya bahwa yurisprudensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap. Untuk pengertian yurisprudensi tetap adalah keputusan hakim yang terjadi karena rangkain keputusan yang serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (standar arresten) untuk mengambil keputusan. Seorang hakim mengikuti keputusan yang terdahulu itu karena, ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa. Menurut Prodjodikoro (2008;5) bahwa hukum semacam ini juga dinamakan case law, yaitu hukum yang perumusannya di dasarkan pada apa yang tampak dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Bahkah, menurut ahli hukum Inggris A.V Dicey, dalam hubungan ini menyatakan bahwa: kekuasaan hakim pada hakikatnya bersifat legislatif (essentially legislative authority of judges) (Budiardjo,2008;351). Jika sistem hukum Eropa Kontenintal sebelum Perang Dunia Kedua secara kaku berpegangan kepada sistem kodifikasi, maka kini sistem-sistem itu lebih
I Gusti Ngurah Santika, SPd
483
memberi perhatiannya kepada cara-cara pembentukan hukum oleh penguasa (belissingenleer) dan pengadilan-pengadilan (jurisprudentie. Sebaliknya sistem-sistem Anglo-Amerika, yang sebelumnya menggunakan azas staire dececis atau case-law, melihat bahwa menggantungkan diri pada cara ini akan menimbulkan hukumnya ketinggalan dengan perubahan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya; sehingga kinipun negara-negara ini telah berpegangan pada undang-undang, yang kebanyakan di Inggris merupakan kompilasi (kumpulan kaedah-kaedah yang telah diciptakan oleh yurisprudensi ditambah dengan beberapa kaedah-kaedah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini) (Hartono,1982; 103-104). Berkaitan dengan sejarah negara hukum yang menganut konsep rechtstaat dengan rule of law, Philipus M. Hadjon (dalam Ridwan HR,2011;4) menyatakan bahwa. Konsep rechtstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law atau Modern Roman Law, sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah administratif sedangkan common law adalah judicial. Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan administrasi, sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinentallah mula pertama cabang hukum baru disebut droit administratif adalah hubungan antara administrasi dengan rakyatdi Kontinen dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara Dengan demikian, jika kita memetakan berdasar sejarah dan kawasan, maka ada dua tradisi dan sistem hukum yang melahirkan konsepsi negara hukum, yaitu: 1. Tradisi Eropa Kontinental dengan civil law yang menekankan pada hukum tertulis agar terdapat kepastian hukum. Negara hukumnya disebut rechtsstaat. 2. Tradisi Anglo Saxon dengan common law yang menekankan pada yurisprudensi guna mencapai penegakan rasa keadilan. Negara hukumnya disebut the rule of law (Mahmud MD,2009;256).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
484
Indonesia pun merupakan negara hukum, bahkan sebelum diamandemen UUD 1945, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Penjelasannya dengan menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Namun, kiranya pengertian dalam Penjelasan terkait dengan konsep negara hukum, seperti apa yang dianut oleh Indonesia tentunya masih relevan untuk sekarang, hanya saja pengertian konsep yang dianut tersebut, perlu ditambah lagi dengan ajaran negara hukum materiil (rule of law), bunyi Penjelasan tersebut, yaitu sebagai berikut. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah: I. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat). 1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). II. Sistem Konstitusional. 2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sementara itu penggunaan istilah rechtstaat dihapus dari Undang-Undang Dasar Negara kita sejalan dengan peniadaan unsur Penjelasan setelah Undang-Undang Dasar negara kita itu dilakukan empat kali perubahan dalam satu rangkaian perubahan. Istilah resmi yang dipakai sekarang, seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum yang bisa menyerap substansi rechtstaat dan the rule of law sekaligus. Unsur konsepsi negara hukum yang berasal dari tradisi Anglo Saxon (the rule of law) di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(MPR RI,2011;67). Sebenarnya di dalam UUD 1945 juga terdapat ciri daripada negara hukum sebagaimana dimaksudkan di atas, seperti dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang kemudian menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Sehingga dalam ketentuan itu tidak hanya kemudian tersimpul hak asasi saja, melainkan juga tidak melepaskan kewajiban asasi sebagai pendamping utamanya. Sehingga dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut, telah menganut konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang harus dimiliki warga negara Indonesia termasuk pula dalam hal ini adalah terhadap pemerintahnya. Selain itu, dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 khususnya berkaitan dengan unsur-unsur untuk dapat kemudian dikatakan sebagai suatu negara hukum telah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
485
diupayakan semaksimal mungkin. Berbagai materi yang berkaitan dengan unsur-unsur negara hukum telah pula dimasukan pada saat Perubahan UUD 1945. Hal mana terlihat dengan jelas setelah Perubahan Kedua UUD 1945, di mana kemudian ditambahnya materi yang begitu banyak, terutama berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, ternyata hanya terdiri satu pasal saja, yang tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945, itu pun nantinya masih harus diatur kembali dalam bentuk undang-undang sebagai aturan operasionalnya. Sehingga terlihat bahwa konstitusi ketika itu sebenarnya tidaklah sepenuhnya memberikan jaminan hak asasi manusia, terutama tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di depan umum. Melainkan, hak tersebut merupakan pemberian daripada dua lembaga negara (DPR dan Presiden) sebagai pembentuk undang-undang, untuk sampai dengan di mana batas-batas terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, akan dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Bahkan, berkaitan dengan pengaturan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, walaupun dalam konstitusi sudah ditegaskan untuk diatur kembali dalam bentuk undang-undang, namun pada waktu itu tampaknya penguasa sendiri enggan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Hal mana dikarenakan mulai dari UUD 1945 disahkan oleh PPKI (ditetapkan) sampai dengan 1998 belumlah ada pengaturan, berkaitan dengan hak-hak asasi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945, yang memang seharusnya diatur kembali lewat undang-undang. Semua itu kemudian membawa konskuensi bagi lahirnya pemerintahan yang secara substansif tidak demokratis dan membuka peluang bagi dilakukannya berbagai pelanggaran HAM (Mahmud MD,2001;137). Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 barulah kemudian berkaitan dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945, dilaksanakan dengan membentuk Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, yang selanjutnya dapat menjamin kebebasan setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya di depan umum. Kemudian, jaminan hak asasi manusia sebenarnya barulah dapat dikatakan, setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, khususnya pada perubahan kedua, di mana hasil perubahan terhadap UUD 1945 tersebut selanjutnya dengan tegas menggariskan hak-hak asasi. Hak asasi manusia tercantum mulai dari ketentuan Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945, yang kemudian semakin menegaskan kedudukan Indonesia sebagai suatu negara dengan peletakan hukum pada tempat tertinggi untuk melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 setelah diamandemen memang benar-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
486
benar merupakan hak konstitusional yang tidak dapat disepelekan begitu saja oleh penguasa. Walaupun dalam kenyataannya, hak-hak asasi manusia tersebut perlulah diadakan pembatasan nantinya, pembatasan tersebut kemudian akan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tidak lain semata-mata sebagai suatu negara demokrasi, maka setiap orang tentunya memiliki hak yang sama untuk kemudian benarbenar dijamin dalam konstitusi. Dengan demikian, hak orang lain, pada hakekatnya adalah suatu kewajiban bagi kita untuk menghormati hak tersebut. Oleh karena itu, dengan jelas dapat diketahui bahwa untuk sekarang, negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Karena UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah memenuhi ciri khas negara hukum yang demokratis, yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, perlu untuk diketahui bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil, bukan negara hukum seperti apa yang kemudian diciptakan oleh Immanuel Kant, yaitu negara hukum dalam pengertian sempit, klasik, atau kuno, yaitu negara di mana tugas negara hanya menjaga keamanan dan ketentraman dengan membuat hukum, melaksanakan hukum, dan mengawasi pelaksanaan hukum tersebut. Sedangkan tugas-tugas lainnya seperti tugas dalam bidang pendidikan dan pengajaran, keagamaan, pertanian dan lain sebagainya menjadi tugas para warga negara perorangan (Soehino,1985;22). Dengan kata lain, menurut Asshiddiqie dan Syahrizal (2012;110) bahwa dalam kondisi sekarang, perlu kiranya kita mengembangkan pemahaman mengenai konsep negara kesejahteraan yang demokratis melalui pematangan liberalisasi politik, seiring dengan upaya mengimbangi liberalisasi ekonomi dengan kebijakan kesejahteraan berorientasi kolektif. Sekilas, kebijakan ini tampak seperti sebuah reaksi terhadap praktek politik sebelumnya dan roda pun terus bergulir membentuk putaran yang sempurna. Namun, kemiripannnya lebih terlihat nyata dibandingkan dengan hal yang sebenarnya. Kolektivisme tak hanya terinspirasi oleh motif-motif humaniterianisme-sistem merkantil jelas sama sekali ada hubungannya dengan motif humaniterianisme-namun kebijakan baru ini terus memperluas upayanya untuk menyelamatkan negara dari kerusakan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan (yang belum dikenal dalam era sebelumnya) yang menganggap demokrasi politik itu sendiri tidak bermanfaat dan mengingkari kemampuan demokrasi politik untuk mencapai kepentingan materi rakyat yang sebenarnya (Strong,2005;447). Ini adalah sesuai dengan salah satu ciri daripada negara kesejahteraan, yang menurut Soekanto (2008;313) bahwa peranan negara tidak hanya terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban belaka, akan tetapi negara secara aktif berperanan di
I Gusti Ngurah Santika, SPd
487
dalam penyelenggaraan kepentingan-kepentingan di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya. Hal berarti tidak sesuai hanya dengan menghapuskan peranan negara dalam pengaturan kehidupan masyarakat kecuali dua hal yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban, dan melindungi kedaulatan negara (Atmasasmita,2007;6). Hal ini dikarenakan menurut Brotodihardjo (1998;8-9) bahwa dari zaman ke zaman, menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakan berbagai tugas yang berguna dalam masyarakat. Oleh karena itu tugas negara yang mewakili kepentingan bersama menjadi lebih luas dalam mengusahakan peningkatan kemakmuran yang adil dan merata (Welfare state) (Harsono,2008;61). Negara hukum Indonesia dapatlah kita masukan dalam katagori negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas. Hal mana dapat kemudian diketahui dari perumusan mengenai tujuan Indonesia untuk bernegara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alenia IV, pada dasarnya telah menunjukan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum materiil. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Mahmud MD (2010;259) menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara hukum materiil atau welfare state yang pada dasarnya mewajibkan pemerintah membangun kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan kepentingan umum. Dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alenia ke IV, telah menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Untuk memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (kursif penulis). Selain adanya alenia ke empat UUD 1945 tersebut di atas, untuk lebih menegaskan kembali bahwa negara Indonesia adalah suatu negara hukum materiil, selanjutnya Pembukaan UUD 1945 dijabarkan kembali pada pasal-pasal UUD 1945, khususnya pada ketentuan Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Ketentuan tersebut merupakan cerminan utama bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dengan menganut konsep kesejahteraan rakyat yang memang paling diutamakan (welfare state). Dibawah ini merupakan bunyi dari ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yang merupakan cerminan langsung, bahwa
I Gusti Ngurah Santika, SPd
488
negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang demokratis dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat, untuk kemudian direalisasikan oleh negara, khususnya pemerintahan. Pasal 33 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. Pasal 34 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang (kursif penulis). Bahkan oleh Sri-Edi Swasono (dalam Rahardjo,2009;84) disalah satu tulisannya menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah suatu Raksasa. Ditetapkannya Pasal 33 UUD 1945 merupakan wujud Nasonalisme Ekonomi Indonesia, yaitu merupakan tekad kemerdekaan untuk mengganti asas kolonial, yaitu asas perorangan (individualisme) menjadi asas nasional, yaitu kebersamaan dan asas kekeluargaan (mutualisme and brotherhood). Sebenarnya, UUD 1945 memiliki unsur-unsur yang menandakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum materiil Tentunya negara hukum Indonesia berbeda dengan negara hukum formal yang dianut oleh negara lain, karena negara lain hanya mendasarkan pada hukum semata. Hal ini terjadi dikarenakan adanya berbagai perbedaanya, seperti latar belakang sejarahnya (historical background), sosial politik,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
489
budaya, perkembangan ekonomi dan lain-lainnya, telah menyebabkan perbedaan yang mendasar antara negara hukum pada negara lainnya dengan di Indonesia. Sehingga negara Indonesia tidak membiarkan rakyatnya untuk saling meniadakan satu sama lain, guna mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, menurut Nasution (2010;79) bahwa dalam dunia sekarang ini hendaknya diutamakan kerjasama dan bukan persaingan. Sekarang tidak lagi berlaku semboyan survival of the fittest, hanya yang kuat yang akan hidup. Dengan demikian jelas sekali bahwa secara konstitusional, negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan (welfare state). Dalam paham negara kesejahteraan, negara turut campur/berperan dalam aktivitas perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat (Magnar dkk,2010;113). Akan tetapi Jika kesejahteraan tidak mampu dalam kenyataan mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara dapat bergeser menjadi negara komunitas atau negara primordial (Atmadja,2012;67). Tidak lain dikarenakan dapat saja melalui campur tangan yang intensif dari negara, memang benar bahwa proses pembangunan akan berjalan lebih massal dan cepat. Namun, campur tangan negara yang cenderung otoriter dan bersifat sangat sentralistis dalam pelaksanaan kebijaksanaan dikhawatirkan di saat yang bersamaan juga akan melahirkan berbagai masalah (Narwoko dan Suyanto,2006;10).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
490
BAB V SEKILAS BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Sejak tahun 1998 para pengamat politik berpandangan bahwa kita memasuki masa transisi dari pemerintahan yang dicap otoriter menuju sistem pemerintahan demokratis dengan masyarakat sipil (civil society) yang akan memainkan peranan utama (Pulukadang dan Sitanggang,2008;1). Pernyataan tersebut kemudian ditandai dengan semakin derasnya tuntutan rakyat terhadap kehidupan yang lebih demokratis, di samping tentunya mampu memberikan jaminan kebebasan yang mendasar bagi warga negara dalam berhadapan dengan penguasa. Untuk itu, UUD 1945 sebagai jaminan mendasar bagi kehidupan rakyat terutama kebebasannya untuk kemudian berhadapan secara langsung dengan pemerintah, khususnya dalam kehidupan bernegara, merupakan sasaran utama yang selanjutnya menjadi tuntutan rakyat agar dilakukan perubahan. Walaupun pada mulanya timbul suatu keraguan, terkait dengan keberhasilan daripada tuntutan rakyat akan perubahan/amandemen terhadap UUD 1945. Timbulnya keraguan tersebut tidak lain dikarenakan adanya situasi dan kondisi yang ketika itu, memang sempat menimbulkan keragu-raguan terutama dari berbagai kalangan yang menghendaki adanya perubahan terhadap UUD 1945. Namun, keragu-raguan tersebut akhirnya tidak terbukti, karena adanya tuntutan rakyat yang begitu deras, telah menyebabkan keragu-raguan tersebut tidak bisa menghalangi arus dari demokratisasi yang datang bertubi-tubi untuk menuntut dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Tuntutan demokratisasi terhadap UUD 1945 bertujuan untuk menjamin kehidupan rakyat agar lebih demokratis lagi, sehingga nantinya tidak diselewengkan lagi oleh penguasa seperti pada era sebelumnya. Hal mana terbukti dengan adanya tuntutan perubahan terhadap UUD 1945, dari rakyat Indonesia sehingga pada akhirnya telah membuahkan suatu hasil yang kemudian dapat dipandang cukup menggembirakan. Dikarenakan akhirnya Perubahan UUD 1945 yang merupakan tuntutan utama rakyat tersebut, ternyata dapat dilaksanakan oleh MPR dengan hikmat. Bahkan, perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 oleh MPR tersebut, adalah bersifat menyeluruh dan total, sehingga dapat kemudian dikatakan telah mengubah sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan menjadikannya sangat berbeda dengan UUD 1945 sebelum diamandemen. Perubahan UUD 1945 yang pertama sampai dengan keempat jelas bersifat mendasar dan mencakup materi yang sangat banyak, sehingga telah mengubah sistematika, baik perumusan formalnya maupun sistematika berpikir UUD 1945
I Gusti Ngurah Santika, SPd
491
(Huda,2008;375). Dengan demikian, dirubahnya UUD 1945 secara besar-besaran, tentunya juga harus diikuti pula dengan adanya perubahan makna, yang juga harus dilakukan secara mendasar, sehingga pastinya berbeda pula dengan sebelumnya. Besarnya perubahan UUD 1945, yang dilakukan MPR telah menyiratkan bahwa perubahan UUD 1945, mendekati/menjadikan UUD 1945 sebagai UUD yang baru. Berkaitan dengan perubahan terhadap UUD 1945, Asshiddiqie (2009;297) kemudian menyatakan bahwa dari segi kuantitatif saja sudah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya UUD 1945 setelah mengalami empat kali perubahan, sudah berubah sama sekali menjadi konstitusi yang baru. Hanya nama saja yang dipertahankan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan isinya sudah berubah secara besar-besaran. Padahal dalam melakukan perubahan sudah ada suatu kesepakatan, bahwa perubahan dilakukan dengan cara addendum. Yang berarti mengubah ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman untuk mewujudkan negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dengan tetap mempertahankan ketentuan yang lama, selama ketentuan tersebut sesuai dengan kehidupan negara demokratis. Dengan nada yang sama Azhary (2006;166) kemudian menyatakan bahwa pada mulanya amandemen UUD 1945 dilakukan untuk melakukan demokratisasi terhadap UUD 1945. Tetapi dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan politik nasional pasca Pemilu 1999 terjadi perubahan paradigma amandemen UUD 1945 bukan sekedar untuk demokratisasi tetapi ke arah perubahan sistem pemerintahan. Sehingga semangat yang mendasari pada mulanya hanya untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah demokratisasi, namun tampaknya terlihat telah terjadi perubahan pandangan di MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan pandangan MPR yang sebelumnya menjadi dasar, ternyata kemudian menjadi berbeda dengan apa yang dianutnya pada saat melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Pandangan baru itulah kemudian, dijadikan dasar utama di samping sebagai semangat dalam melakukan demokratisasi terhadap UUD 1945. Pada awalnya demokratisasi UUD 1945 sendiri merupakan suatu usaha untuk mengembalikan sistem pemerintahan sesuai dengan ide kedaulatan rakyat itu sendiri yang berdasarkan hukum. Sistem pemerintahan yang dijadikan sasaran perubahan merupakan suatu awal dalam rangka menata cabang-cabang kelembagaan negara, tentunya dengan tujuan agar tercipta mekanisme checks and balances yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, di samping dengan tujuan utamanya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Perubahan tersebut meliputi sistem pelembagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan negara yang utama (legislatif, eksekutif, dan yudisial), sistem pemerintahan lokal, pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang lebih rinci (Jundiani,2010;7).
I Gusti Ngurah Santika, SPd
492
Bahkan, UUD 1945 sebagai peraturan yang berkedudukan paling tinggi dalam negara Indonesia, yang juga merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan negara, termasuk pula sebagai dasar aturan lembaga negara untuk melakukan tugasnya, yang tentunya semuanya sudah diatur dengan tegas disertai suatu mekanismenya dalam kerangka checks and balances, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUD 1945. Tanpa adanya jaminan akan perimbangan kekuasaan tersebut, lembaga negara yang memiliki kekuasaan tertinggi, dapat saja kemudian menggunakan kekuasaannya secara tidak terbatas, paling tidak pada akhirnya penyelewengan dalam bentuk penyalagunaan kekuasaan (abuse of power) hanya tinggal untuk menunggu waktu saja. Sehingga, reformasi kelembagaan merupakan suatu hal yang sifatnya mendesak untuk dilakukan, khususnya berkaitan dengan pengaturan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam UUD 1945. Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini (Soeprapto,tt;19). Tentunya diharapkan ke depannya dengan adanya reformasi kelembagaan, yang didahului dengan reformasi peraturan perundang-undangan tertinggi, yang dalam hal ini adalah konstitusi, akan membawa dampak lebih baik bagi kehidupan negara, khususnya dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, hukum dan yang lainnya. Namun demikian, tampkanya perubahan itu belum dapat sepenuhnya menjamin terlaksananya proses perubahan arah tatanan hukum maupun politik apabila tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (Affandi,2006;2). Tidak lain disebabkan bahwa pada saat proses Perubahan UUD 1945 oleh MPR, ternyata tidak banyak melibatkan peran rakyat, terutama dalam memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, terkait dengan materi apa saja yang menurut rakyat seharusnya dirubah ataupun untuk dicantumkan dalam UUD 1945. Sehingga Perubahan UUD 1945 yang sebetulnya menjadi harapan rakyat banyak, untuk dapat mencapai tujuan negara yang sudah lama diidamidamkan selama ini, hanyalah menjadi ajang perebutan bagi elit politik, untuk menjadikan aspirasinya yang berwujud kepentingan-kepentingannya itu paling utama, bahkan dapat mengalahkan aspirasi rakyat, tentu saja agar kepentingan elit tersebut nantinya dapat terakomodasi ke dalam UUD 1945. Upaya tersebut dapat dicapainya, tentunya hanya dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945 secara drastis, terkait dengan materi dalam bidang ketatanegaraan. Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan secara drastis, berarti telah berhasil mengubah hal-hal mendasar terkait dengan sistem ketatanegaraan, yang tentunya berbeda kemudian dengan sebelum adanya perubahan. Berkaitan dengan hasil amandemen UUD 1945 yang berimplikasi terhadap ketatanegaraan, maka Winardi (2008;25) berpendapat bahwa dari substansi, hasil amandemen belum menyentuh beberapa persoalan ketatanegaraan yang mendasar, sehingga belum membawa kearah perubahan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
493
fundamental, misalnya tentang asas negara hukum, asas demokrasi dan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas fundamental bernegara belum terakomodasi dalam amandemen di samping itu juga berpeluang memunculkan ketegangan antar lembagalembaga negara serta sistematika UUD 1945 pasca amandemen terkesan amburadul. Alasan utama yang menyebabkan hal tersebut, dikarenakan perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR adalah bersifat tambal sulam. Ditambah kemudian belum adanya kesiapan dari pihak MPR, untuk melakukan perubahan secara komperhensif, menyebabkan perubahan yang dihasilkan menimbulkan ketidakpuasan berbagai kalangan. Dapatlah dikatakan berkaitan dengan ketidakpuasan tersebut, dapat dilihat daripada pro dan kontra yang timbul, dikarenakan hasil daripada amandemen UUD 1945, terutama di kalangan para pakar yang tentunya telah menimbulkan perdebatan berkepanjangan. Peristiwa tersebut ternyata juga diakui oleh Soeprapto (2007;125) yang dalam pendapatnya menyatakan bahwa walaupun masalah Perubahan UUD 1945 sampai hari saat ini masih menimbulkan perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara para pakar di bidang politik, hukum, dan bidang-bidang yang menyangkut masalah kenegaraan, baik perbedaan tentang proses pembentukannya maupun materi yang terkandung di dalam Perubahan UUD 1945. Dengan demikian, tentunya hal tersebut akan menyebabkan dampak yang negatif terhadap pemasyarakatan daripada makna UUD 1945 yang baru, karena para pakar masih sibuk tersandera oleh pro dan kontra terhadap hasil perubahan. Dalam hal ini, diperlukan komitmen bersama untuk menyelaraskan persepsi terhadap pengertian-pengertian baru yang terkadung dalam UUD 1945, sehingga kemudian dapat diterima bersama, terlepas adanya perbedaan pandangan yang melatar belakangi pendapat tersebut. Sehingga, hasil Perubahan UUD 1945 tidak hanya hidup dalam tataran teoritis saja, namun perlu juga untuk implementasikan dalam kehidupan nyata, terutama oleh para penyelenggara negara. Sehingga kemudian dapat diketahui lebih lanjut terkait dengan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 setelah dilakukan amandemen sebanyak empat kali dalam satu rangkaian perubahan oleh MPR. Setelah diketahuinya kelemahan yang melekat pasca amandemen terhadap UUD 1945, barulah kemudian seandainya ada momentum yang tepat untuk melakukan perubahan susulan nantinya, maka kita benar-benar sudah siap untuk melakukan perbaikan dengan menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu. Pernyataan tersebut bukannya tanpa dasar, dikarenakan terlihat sekarang adalah lemahnya semangat para penyelenggara negara dalam upaya melaksanakannya secara sungguh-sungguh agar sesuai dengan semangat awal pada saat melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Impelementasi ketentuan yang terdapat dalam amandemen UUD 1945 dirasakan belum nyata hasilnya meskipun telah banyak dibuat dan terbentuknya lembaga-lembaga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
494
baru yang dianggap menjalankan amanat konstitusi negara hasil dari gagasan reformasi (Ratna,2006;105). Sebagain kalangan, terutama rakyat menilai hasil daripada Perubahan UUD 1945 oleh MPR, ternyata masih jauh dari yang dikatakan memuaskan. Ditambah lagi bila implementasikan di lapangan, apalagi jika dilaksanakan secara konsisten, bukannya tidak mungkin di kemudian hari akan menimbulkan banyak permasalahan. Memang hal ini perlu diakui, bahwa terlepas daripada keberhasilan MPR dalam melakukan reformasi konstitusi, namun juga tidak terlepas dari kenyataan bahwa ketidaksiapan MPR dalam menyusun agenda secara komperensif dalam melakukan amandemen UUD 1945. Oleh karenanya, banyak yang memberikan ramalan bahwa hasil amandemen UUD 1945 tidak akan membawa perbaikan yang signifikan, terutama terkait dengan kepentingan rakyat. Karena itu menurut Bambang Widjojanto dalam Huda (2008;375) menyatakan bahwa sejak awal sudah dapat diduga, arah dan substansi perubahan tidak akan mendasar guna mengabdi secara utuh pada kedaulatan rakyat serta membangun sistem kekuasaan yang demokratis dengan cara membenahi carut-marutnya sistem kekuasaan. Hal mana tidak terlepas dari adanya berbagai kepentingan saling tarik menarik, agar selanjutnya dapat diadopsi menjadi materi UUD 1945, yang tentunya materi tersebut hanya memuat kepentingan elitis bersifat sesaat. Sehingga, semangat reformasi yang menjadi momentum dalam melakukan perubahan UUD 1945, yang bersifat mendasar terhadap kehidupan rakyat, agar menjadi lebih baik, dalam kenyataannya hanya diserahkan kepada segolongan elit politik, yang ketika itu sedang berkuasa, untuk selanjutnya memaksakan kepentingannya agar diterima secara formal melalui bentuknya yang baku, yaitu peraturan perundang-undangan tertinggi. Dimana tentunya ke depannya akan menimbulkan polemik berkepanjangan, sehingga pastinya berpotensi mencederai nilai-nilai reformasi itu sendiri, untuk merubah arah kehidupan sebelumnya, yang pada awalnya mengedepankan kekuasaan, menjadikan hukum sebagai panglima. Kenyataan, bahwa bangsa Indonesia masih jauh dari cita-cita karena proses menuju cita-cita bertolak belakang dengan makna dan semangat kemerdekaan sehingga reformasi seakan beerada diujung tanduk (Mamun,2009;265). Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut, dikarenakan hasil pencapaian daripada Perubahan UUD 1945 dalam rangka demokratisasi sebagai wujud utama tuntutan reformasi, ternyata tidak mampu menghasilkan sesuatu yang bersifat signifikan dalam kehidupan rakyat. UUD 1945 pun pada awalnya menjadi sasaran utama pengecaman daripada kaum reformis setelah diadakan perubahan, ternyata tidak mampu merubah situasi kehidupan rakyat sebelumnya, yang menurut rakyat tidak berpihak kepada mereka. Bahkan, terkait dengan hal tersebut, Hartono (2010;23) berpendapat bahwa hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tuntas pada tahun 2002 pada kenyataannya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
495
telah menimbulkan kontroversi, baik dari segi konsepsi, sistem, maupun nilai-nilai dasarnya. Ini merupakan resiko daripada Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, namun hanya bersifat parsial. Ditinjau dari aspek sistematika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu: 1. Pembukaan (preambule); 2. Batang Tubuh; 3. Penjelasan. Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu: 1. Pembukaan; 2. Pasal-Pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 74 pasal, dan 170 ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Berikut ini merupakan tabel UUD 1945, yang di dalamnya memuat perbandingan antara UUD 1945 sebelum amandemen dengan UUD 1945 yang sudah diamandemen, dengan tujuan untuk semakin memudahkan mempelajari hasil Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada periode 1999 sampai dengan tahun 2002, yang pada dasarnya UUD 1945 itu sendiri telah dirubah oleh MPR sebanyak empat kali dalam satu rangkaian perubahan.
Tabel 4.1. Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
I Gusti Ngurah Santika, SPd
496
No.
bab
Pasal
ayat
Aturan Peralihan 4 pasal
Aturan Tambahan 2 ayat
1.
Sebelum perubahan Setelah perubahan
16
37
49
2.
21
73
170
3 pasal
2 pasal
Berikut ini merupakan beberapa hasil daripada amandemen terhadap UUD 1945 selanjutnya juga terkait dengan beberapa masalah ketatanegaraan Indonesia serta problematika baik dalam praktek maupun teori yang kemudian menyertainya. A. Amandemen Pertama Terjadi Pada SidangUmum MPR Tahun 1999 Disahkan, 19 Oktober 1999. Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran Kekuasaan Presiden Dalam Bidang Pembentukan Undang-Undang Pada amandemen pertama terhadap UUD 1945, mempunyai tujuan utama, yaitu untuk mengurangi dan membatasi kekuasaan Presiden pada semua lini kekuasaan yang selama ini dimilikinya, baik itu dalam bidang eksekutif, legislatif mapun yudikatif. Dalam bidang legislatif, di mana sebelumnya Presiden sangat dominan dalam pembentukan undangundang, maka untuk sekarang ini ternyata titik berat kekuasaan pembentukan undangundang, sepintas lalu terlihat telah bergeser dari Presiden ke tangan DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Ketentuan dari pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa DPR sebagai
I Gusti Ngurah Santika, SPd
497
lembaga legislatif untuk sekarang ditentukan bertugas memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tidak lagi berada pada tangan Presiden, yang sebenarnya merupakan lembaga eksekutif. Kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang seperti dinyatakan oleh UUD 1945 sebelum diamandemen, lebih khusus lagi telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, pada dasarnya menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dasar pemikiran adanya pergeseran kekuasaan dari eksekutif kepada legislatif, khsusnya dalam bidang pembentukan undang-undang adalah untuk mengembalikan kekuasaan pembentukan undang-undang ke tangan lembaga legislatif, yang pada dasarnya terdiri dari wakil-wakil rakyat. Bahkan, memang sudah seharusnya bahwa DPR yang merupakan lembaga perwakilan kemudian ditentukan mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan yang mengikat rakyat sendiri. Oleh karena itu, dalam membentuk undang-undang yang pada dasarnya mengikat rakyat, tentunya kemudian rakyat sendiri harus menyetujuinya, walaupun hanya melalui wakil-wakilnya yang memang telah dipilih untuk duduk di DPR. Dengan begitu, selanjutnya diharapkan akan jelas terlihat tanggungjawab lembaga negara, di mana eksekutif merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, betugas menjalankan undang-undang (Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945), sedangkan untuk DPR merupakan lembaga legislatif betugas sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Dengan kata lain, bahwa tanggungjawab di antara kedua lembaga negara tersebut dalam bidang tugasnya masingmasing akan menjadi lebih jelas kemudian. Selain itu, berkaitan dengan fungsi pembentukan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang sudah seharusnya dipisahkan, terutama mengenai organ yang bertugas menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut. Konsep demikian, tentunya akan membawa keuntungan tersendiri, terutama untuk terhindarnya dari potensi tirani, yang jika kemudian menyatukan kedua kekuasaan tersebut hanya dalam satu tangan, seperti sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, tentunya pernyataan tersebut dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia memang sudah terbukti. Inilah selanjutnya yang menjadi pertimbangan utama, dalam rangka memisahkan antara organ yang berfungsi untuk membuat undang-undang, dengan organ yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Sehingga dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih di antara kedua lembaga tersebut, berkaitan dengan fungsinya masing-masing, seperti sebagaimana dimaksudkan di atas. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya juga bermaksud untuk meletakan prinsip-prinsip yang jelas sebagai suatu negara hukum, khususnya berkaitan dengan tanggungjawab daripada lembaga negara yang bertugas untuk menjalankan fungsinya. Sehingga di kemudian hari dengan jelasnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
498
kekuasaan yang dipegang oleh lembaga negara tersebut, akan jelas pula terlihat untuk selanjutnya, kepada siapa hendaknya rakyat nantinya akan meminta pertanggungjawaban, terutama berkaitan dengan tugas-tugas yang memang pada mulanya diserahkan oleh rakyat kepada para penguasa melalui lembaga-lembaga tersebut. Pertanggungjawaban para pemegang kekuasaan lembaga negara tersebut, akan mudah diminta oleh rakyat, jika sebagai pemegang kedaulatan rakyat, rakyat sendiri jelas-jelas mengetahui mengenai prinsip-prinsip pembagian tugas dari lembaga negara tersebut dalam melakukan fungsinya, sehingga menjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan selanjutnya dalam UUD 1945. Tanpa jelasnya tugas yang dimiliki antara kedua lembaga negara tersebut, selanjutnya akan menyebabkan kaburnya prinsip-prinsip negara hukum, bahwa dalam setiap pengambilan suatu keputusan, harus dapat pula dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Namun, jika kemudian dicermati dengan saksama, maka hasil daripada Perubahan Pertama UUD 1945, khususnya berkaitan dengan pengembalian kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dari tangan Presiden kepada DPR ternyata belum tampak terlihat jelas. Tentu tidak jelasnya di sini adalah berkaitan dengan tugas dan wewenang dari kedua lembaga negara tersebut, terutama dalam hubungannya di bidang pembentukan undang-undang, yang mungkin saja kemudian akan berimbas pula, terhadap kaburnya pertanggungjawaban kedua lembaga negara tersebut kepada rakyat. Adanya ketidakjelasan sebagaimana dimaksudkan di atas, adalah berkaitan dengan masih diberikannya kewenangan kepada Presiden, untuk turut campur dalam bidang pembentukan undangundang. Di mana seharusnya tugas Presiden sebagai kepala eksekutif adalah hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 (lihat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Namun, selanjutnya terlihat dalam UUD 1945, ternyata Presiden juga ikut bersama dengan DPR, dalam pembentukan undang-undang melalui pembahasan bersama sampai kemudian tercapai persetujuan bersama. Dengan demikian, pada dasarnya DPR dan Presiden setelah Perubahan UUD 1945, telah ditetapkan sebagai lembaga negara, yang sama-sama memiliki kewenangan dalam bidang pembentukan undang-undang. Sehingga, tanpa adanya keterlibatan daripada kedua lembaga negara tersebut dalam membentuk undang-undang, maka dapat dipastikan tidak akan pernah ada rancangan undang-undang dapat menjadi undang-undang. Dengan demikian, untuk sekarang ini, terlihat bahwa kedudukan antara Presiden dan DPR adalah seimbang dalam proses pembentukan undang-undang. Untuk hal inilah kemudian penulis bermaksud, dengan menyatakan adanya suatu ketidakjelasan tugas dan fungsi antara Presiden sebagai eksekutif, dan DPR merupakan legislatif, dalam melaksanakan kewenangannya masing-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
499
masing. Karena terlihat seimbangnya kedua kekuasaan lembaga negara tersebut dalam pembentukan undang-undang, menyebabkan kemudian tidak dapatlah kita memberikan suatu penilaian dengan tegas, berkaitan dengan kualitas daripada undang-undang, yang dibentuk oleh kedua lembaga negara tersebut. Karena undang-undang merupakan hasil daripada buah kerjasama antara Presiden dan DPR, telah ditentukan oleh UUD 1945 berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Keseimbangan tersebut kemudian terlihat dengan jelas, terutama dalam pembahasan rancangan undang-undang antara DPR dan Presiden, di mana selanjutnya dengan tegas dinyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden, untuk mendapat persetujuan bersama. Tentunya adanya persetujuan bersama merupakan kunci utama, dalam penyelesaian rancangan undang-undang, sehingga menjadi undang-undang. Kata terakhir daripada penyelesaian rancangan undang-undang, adalah terletak pada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang. Tentunya ke depannya diperlukan suatu kesepahaman antara DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang, agar kemudian dapat tercapai kesepakatan dalam bentuk persetujuan bersama di antara kedua lembaga negara tersebut. Kemudian terlihat kembali dikukuhkannya kekuatan daripada persetujuan bersama tersebut dalam ketentuan ayat (3) dari Pasal 20 UUD 1945, dengan memberikan penekanan kembali, bahwa tanpa persetujuan bersama maka dapat dipastikan rancangan undang-undang tersebut, tidak mungkin dapat lagi untuk diajukan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Jadi, ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945, hanyalah menekankan kuatnya persetujuan bersama tersebut, sehingga adanya ketentuan ayat (3) dari Pasal 20 UUD 1945, pada dasarnya telah meletakan penegasan tentang prinsip-prinsip daripada persetujuan bersama, sebagai kekuatan penyeimbang antara DPR dan Presiden, dalam membentuk undangundang. Terlihatlah kemudian bahwa dengan adanya ketentuan ayat (2) dan (3) daripada Pasal 20 UUD 1945, sebenarnya telah ditentukan bahwa bukan hanya DPR berfungsi sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, melainkan juga eksekutif yang notabene juga sekaligus menjalankan fungsi sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana lazimnya. Apakah dengan adanya ketentuan ini merupakan suatu upaya mempertahankan keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membentuk undang-undang? Apakah dengan demikian, dapat kemudian dikatakan tidak bertentangan konsep yang mendasarinya, terutama dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yang memang telah mengamanatkan bahwa untuk pemegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah terletak di tangan DPR? Tampaknya sepintas memang adanya ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUD 1945,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
500
merupakan suatu upaya dalam rangka menjaga keimbangan antara kekuasaan Presiden dan DPR, dalam bidang pembentukan undang-undang, sehingga diharapkan akan tercipta suatu mekanisme checks and balances antara kedua cabang kekuasaan tersebut, terutama dalam membentuk undang-undang. Seimbangnya kekuasaan antara kedua lembaga negara tersebut di atas, dalam membentuk undang-undang telah pula dijelaskan sebelumnya, di mana ditegaskan kembali dalam ketentuan ayat (3) dari Pasal 20 UUD 1945, merupakan suatu konsep dalam kerangka mencapai mekanisme checks and balances. Bahkan, jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat keseimbangan antara Presiden dan DPR dalam ketentuan ayat 3 dari Pasal 20 UUD 1945, yang menyatakan bahwa jika dalam kenyataannya suatu RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang tersebut, tidak dapat diajukan kemudian dalam masa keanggotaan DPR pada periode itu. Dengan kata lain, rancangan undang-undang yang tidak dapat mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, tidak boleh lagi untuk diajukan kembali pada masa keanggotaan DPR periode itu. Namun, tentunya rancangan undang-undang tersebut dapat selanjutnya diajukan pada keanggotaan DPR di periode berikutnya. Dalam ketentuan Pasal 20 UUD 1945, sebenarnya terlihat kontradiksi sendiri antara apa yang kemudian menjadi dasar pemikiran utama yang selanjutnya melatarbelakangi ide perubahan, dengan apa yang akhirnya menjadi hasil daripada perubahan UUD 1945. Jika, disimak kembali dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, ternyata adanya pengaturan tersebut, disatu pihak telah mempertegas kekuasaan DPR, sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun pada pihak lain ternyata dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 justru kemudian memperlemah posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undangundang. Tentunya ini merupakan suatu kontradiksi yang terjadi di dalam tubuh UUD 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tersebut, dengan ayat-ayat selanjutnya. Terlihat kemudian dalam ketentuan ayat (1) Pasal 20 UUD 1945, di mana DPR ditentukan memiliki kekuasaan dalam bidang membentuk undang-undang, namun selanjutnya dalam ketentuan ayat (2) dari Pasal 20 UUD 1945, ternyata ditentukan bahwa setiap rancangan undang-undang hanya dapat menjadi undang-undang jika nantinya mendapatkan persetujuan bersama. Persetujuan bersama merupakan suatu bentuk daripada kehendak antara Presiden dan DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang. Keterlibatan Presiden dalam bidang pembentukan undang-undang, merupakan suatu pengturan tidak lazim dalam sistem ketatanegaraan yang dikenal di dunia, apalagi jika kemudian dikatakan bahwa negara tersebut menganut sistem pemisahan kekuasaan di antara lembaga negara. Dengan demikian, dalam UUD 1945 ternyata telah menentukan,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
501
bahwa satu lembaga/organ memiliki dua kewenangan atau fungsi, hal mana akan dapat kita lihat kembali dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUD 1945, hal mana merupakan bentuk keterlibatan Presiden sebagai lembaga negara eksekutif, untuk ikut pula berkecimpung dalam pembentukan undang-undang. Tentunya kewenangan Presiden tersebut di atas, tidaklah dapat begitu saja untuk di kesampingkan, padahal lazimnya untuk eksekutif tugas utamanya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban utamanya, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dengan melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, maka akan tampak kemudian, bahwa kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya berkaitan dengan pembentukan undang-undang kepada Presiden, adalah suatu kewenanga bersifat tambahan. Hanya saja kewenangan yang kemudian dimiliki Presiden dalam keterlibatannya di bidang pembentukan undang-undang, dalam kenyataannya mampu mengimbangi lembaga legislatif, yang sesungguhnya telah ditentukan sebagai pemegang kekuasaan dalam bidang pembentukan undang-undang, sebagaimana terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan masalah tersebut di atas, tidaklah dapat dikatakan dengan sepenuhnya bahwa Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam sistem ketatanegaraannya. Karena jika kita lihat kembali dalam ketentuan Pasal 20 UUD 1945, yang menjelaskan dengan tegas mengenai hubungan antara Presiden dan DPR dalam bidang pembentukan undang-undang. Tidak lain, dalam kenyataannya telah ditentukan di sana bahwa terkait dengan bidang pembentukan undang-undang yang merupakan satu fungsi, ternyata oleh UUD 1945 agar kemudian dijalankan oleh dua lembaga negara tersebut, hal mana pada dasarnya kedudukannya dan fungsinya berbeda, Bahkan satu fungsi yang dilaksanakan oleh kedua lembaga negara tersebut diharuskan, karena tanpa adanya keterlibatan daripada kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang, tidak akan pernah ada suatu rancangan undang-undang yang kemudian dapat diselesaikan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, jika ditelusuri kembali dari pemaparan penulis, terkait dengan kerjasama DPR dan Presiden dalam bidang pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat kemudian dikatakan bahwa konsep yang selanjutnya dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sistem pembagian kekuasaan (distribution of power). Dengan demikian, jelaslah kemudian bahwa DPR bukan sebagai pemegang sepenuhnya kekuasaan dalam bidang pembentukan undang-undang, tetapi dalam memegang kekuasaannya tersebut, oleh UUD 1945 tepat dalam ketentuan Pasal 20 pada dasar telah mengariskan keterlibatan Presiden sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran tidak kalah menentukannya dibandingkan dengan DPR. Artinya tidak hanya DPR
I Gusti Ngurah Santika, SPd
502
yang mempunyai kekuasaan (fungsi) membentuk undang-undang (lewat persetujuannya), namun Presiden dalam kenyataannya ditentukan pula sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang (lewat persetujuannya). Hal mana pada dasarnya, tugas yang dilakukan oleh kedua lembaga negara tersebut terletak pada bidang legislatif, padahal Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif seharusnya hanya bertugas untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Ketentuan lainnya dalam UUD 1945, yang kemudian memperlihatkan kembali besarnya kekuasaan Presiden, dalam bidang pembentukan undang-undang adalah adanya ketentuan yang memberikan hak kepada Presiden, dalam bidang pengajuan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam bentuk hak untuk mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, merupakan salah satu hak konstitusional Presiden yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan adanya hak ini, tentunya terlihat bahwa Presiden yang mengajukan rancangan undang-undang selanjutnya harus diterima oleh DPR untuk dibahas, dengan tujuan utamanya untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, yang selanjutnya tercermin dalam pembahasan rancangan undang-undang. Ternyata dengan adanya ketentuan tersebut, telah membuka suatu peluang untuk memungkinkan terjadinya benturan antara hak konstitusional Presiden, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, untuk mengajukan rancangan undangundang, dengan ketentuan Pasal 21 UUD 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Dalam pada itu, tampak berbeda dengan ketentuan selanjutnya dalam undang-undang, yang bertugas untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22A UUD 1945). Ternyata ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa pembentuk undang-undang telah mengubah kata hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ketentuan Pasal 21 UUD 1945, kemudian menjadi kata dapat. Dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Dengan demikian, jalan keluar untuk mengatasi benturan antara ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 21 UUD 1945, maka untuk itu, dalam UU No. 12 Tahun 2011 kata berhak kemudian diganti menjadi dapat. Dalam pada itu, jika selanjutnya kata berhak diganti menjadi kata dapat, tentunya akan memiliki makna berbeda pula antara apa yang kemudian dimaksudkan oleh UUD 1945 dengan UU No. 12 Tahun 2011. Kata berhak tentunya memiliki kekuatan berbeda dengan kata dapat. Ternyata dalam undang-undang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
503
pun, ditentukan bahwa kedudukan yang dimiliki antara Presiden dan DPR adalah sama terkait dengan pembentukan undang-undang, termasuk pula di dalamnya yang berkaitan dengan bidang pengajuan rancangan undang-undang, telah ditentukan untuk diajukan oleh kedua lembaga negara tersebut. Dengan demikian, tidak ada keharusan daripada kedua lembaga negara tersebut, untuk mengajukan rancangan undang-undang, bahkan tidak ada keharusan/kewajiban untuk menanggapi rancangan undang-undang yang datang tersebut dengan mengadakan sidang untuk selanjutnya dibahas bersama, dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sehingga, rancangan undang-undang yang diajukan kepada DPR selanjutnya akan diterima Presiden, kemudian akan dibahas bersama, apabila kemudian Presiden berkehendak untuk membahasnya bersama DPR, agar nantinya mendapatkan persetujuan bersama, begitupun juga sebaliknya. Selanjut kita kembali sejenak ke dalam UUD 1945, terkait dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dengan ketentuan Pasal 21 UUD 1945, tentunya bisa saja dikemudian hari menimbulkan benturan hak, di antara kedua institusi tersebut, khususnya dalam bidang pengajuan rancangan undang-undang. Jika seandainya nanti adanya benturan antara hak Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang, dengan DPR yang dilain pihak telah ditentukan pula memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Namun, ternyata rancangan undang-undang yang diajukan kedua lembaga negara tersebut adalah mengenai materi sama, maka rancangan undang-undang yang manakah kemudian dipakai atau dibahas dalam sidang paripurna untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama? Ternyata jalan keluarnya tersebut, telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 UU No. 12 Tahun 2011, yang betujuan untuk mengatasi kelemahan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 UUD 1945, terkait dengan adanya potensi benturan hak antara Presiden dan DPR dalam bidang pengajuan rancangan undang-undang. Dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalamnya ditentukan bahwa Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Jika dicermati dengan saksama berkaitan dengan ketentuan tersebut, sepintas lalu terlihat bahwa DPR memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, bila dibandingkan dengan Presiden dalam hal pengajuan rancangan undangundang. Tetapi besarnya kekuasaan DPR dalam hal tersebut ternyata dibatasi, jika saja nantinya suatu rancangan undang-undang yang diajukan antara DPR dan Presiden adalah mengatur mengenai materi sama. Apakah pengaturan demikian yang kemudian dimaksudkan oleh UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
504
undang-undang? tentunya pernyataan tersebut adalah tidak sesuai dengan maksud daripada UUD 1945, tepatnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Jadi, UU No. 12 Tahun 2011 telah menentukan bahwa DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undangundang, kekuasaan tersebut terbatas, yaitu hanya dalam bidang pengajuan rancangan undang-undang yang pada dasarnya mengatur mengenai materi sama. Karena selanjutnya berkaitan dengan materi rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, kemudian akan digunakan sebagai bahan persandingan. Pernyataan tersebut tentunya akan berbeda sekali pengertiannya, apabila pada suatu saat terjadinya pengajuan rancangan undangundang antara DPR dan Pemerintah ataupun sebaliknya, namun ternyata mengatur mengenai materi berbeda, yang berarti dapat saja kedua rancangan undang-undang tersebut, dapat diajukan untuk selanjutnya dibahas oleh kedua lembaga negara tersebut, agar mendapatkan persetujuan bersama. Dengan demikian, tidaklah tampak dengan jelas kekuasaan DPR, seperti yang telah ditentukan dalam UUD 1945, tepatnya ketentuan dari 20 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, yang mana seharusnya menentukan kata akhir dalam setiap pembentukan undang-undang. Pernyataan tersebut, sudah seharusnya berlaku, tidak hanya berkaitan dengan materi sama, seperti yang kemudian diajukan oleh DPR dan Presiden. Karena hal itu, belumlah bisa untuk selanjutnya dikatakan, bahwa DPR sebagai lembaga legislatif merupakan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Karena tetap saja, berkaitan dengan rancangan undang-undang walaupun dalam kenyataannya mengatur materi sama, baik karena rancangan undang-undang tersebut, merupakan usul dari DPR yang kemudian akan dibahas, namun pada akhirnya tetap saja diperlukan persetujuan dari Presiden, terkait dengan materi yang terdapat dalam rancangan undang-undang dari DPR tersebut. Tidak lain, karena telah ditentukan bahwa setiap rancangan undang-undang, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dalam kenyataannya telah memberikan legitimasi, bagi keterlibatan Presiden dalam pembahasan rancangan undangundang bersama dengan DPR, untuk selanjutnya memberikan persetujuannya. Hanya saja, rancangan undang-undang dari DPR tersebut, pembahasannya diprioritaskan daripada rancangan undang-undang yang datang dari Presiden, tetapi ketentuan tersebut dibatasi hanya berkaitan dengan materi rancangan undang-undang yang sama. Namun, agar menjadi undang-undang, ternyata selanjutnya tetap saja rancangan undang-undang tersebut, memerlukan persetujuan bersama daripada kedua lembaga negara tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Bisa jadi, dalam kenyataannya rancangan undang-undang yang kemudian dijadikan bahan sandingan oleh DPR, dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
505
kenyataannya lebih mendominasi isi undang-undang yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan sangat tergantung daripada kualitas materi rancangan undang-undang yang diusulkan oleh kedua lembaga negara tersebut. Namun, tidak kalah pentingnya adalah kekuatan politik yang mendukungnya. Karena ini adalah masalah politik, dimana yang menjadi unsur utamanya bahkan harus ada adalah dukungan suara. Dengan demikian, Presiden sebagai lembaga eksekutif, ternyata oleh UUD 1945 telah diberikan kewenangan di bidang legislasi, dalam bentuk pengajuan rancangan undangundang maupun untuk pembahasannya dengan DPR, sampai akhirnya kemudian tercapai persetujuan bersama dalam sidang paripurna. Walaupun penegasan kekuasaan Presiden dalam bidang pembentukan undang-undang, seperti ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, bahwa Presiden berhak untuk mengajukan RUU meskipun ditentukan oleh undang-undang hanya bersifat sekunder, sebagaimana kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 51 UU No. 12 Tahun 2011, dalam kenyataannya hal tersebut, hanya terkait dengan rancangan undang-undang yang menyangkut materi sama antara DPR dan Presiden, pada saat kedua lembaga negara tersebut, sama-sama mengajukan rancangan undang-undang. Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk ikut mengajukan, di samping terlibat pula dalam pembahasan rancangan undang-undang, sampai akhirnya tercapai suatu persetujuan bersama, untuk kemudian menjadi undang-undang, tentunya memiliki makna yang penting. Hal mana selanjutnya hanya dapat dimengerti, apabila kemudian kita mengetahui bahwa dengan besarnya jumlah tenaga ahli yang ada dilembaga eksekutif di samping dengan jangkauan wilayah begitu luas, bahkan paling pertama yang mengetahui keadaan riil di lapangan, sehingga berdasarkan hal tersebut agar cepat mengambil tindakan, maka perlulah kemudian Presiden diberikan hak untuk mengajukan RUU. Meskipun dengan demikian, dapatlah kemudian dikatakan bahwa hanya Indonesia dengan sistem ketatanegaraannya memberikan kekuasaan legislatif kepada Presiden, untuk ikut mengajukan RUU ke DPR, di samping terlibat bersama untuk membahasnya, bahkan telah ditentukan bahwa rancangan undang-undang tersebut, hanya dapat menjadi undang-undang, jika kemudian ada persetujuan dari Presiden. Dengan ikut terlibatnya Presiden dalam hal mengajukan suatu rancangan undang-undang, maupun keikutsertaannya selanjutnya dalam pembahasannya sampai kemudian pada tercapainya suatu persetujuan bersama. Merupakan upaya yang mungkin dapat memberikan kesempatan kepada Presiden, untuk mengatur hal-hal yang memang dibutuhkan Presiden dalam menjalankan penyelenggaraan bernegara, untuk menjalankan tugasnya agar dapat mewujudkan tujuan negara. Karena, tidak lain dapatlah kemudian dikatakan, bahwa dalam melaksanakan setiap tugas, tentunya tindakan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
506
pemerintah memerlukan legalitas untuk dapat menjamin kepastian hukum (rechtzekerheid), terutama dalam bentuk undang-undang, yang memang untuk itu dapat segera diajukan kepada DPR, sehingga selanjutnya dibahas bersama sampai akhirnya mendapatkan persetujuan bersama. Apalagi negara yang mengaku telah menganut konsep negara hukum, di mana tanpa adanya dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, maka pemerintah tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya, khususnya dasar hukum yang berbentuk undang-undang, sebagai wujud utama daripada hukum tertulis. Oleh karena itu, diperlukan kecepatan waktu untuk mengatur hal-hal yang sebenarnya menjadi kebutuhan Presiden untuk dapat menjalankan pemerintahan. Tentunya dengan anggapan bahwa hanya Presiden yang kemudian lebih mengetahui dan menyadari akan kebutuhannya sendiri. Dikarenakan pada dasarnya tugas Presiden sebagai lembaga eksekutif, adalah pelaksana undang-undang untuk memperlancar jalannya pemerintahan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, terkait dengan rancangan undang-undang yang memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, maka diperlukan kerjasama agar rancangan undang-undang tersebut, dapat terbentuk menjadi undang-undang, sebagai wujud utama daripada kekompakan Presiden dan DPR, tercermin kemudian lewat persetujuan bersama. Berkaitan dengan adanya persetujuan bersama dalam pembentukan undang-undang, artinya jika tidak ada persetujuan bersama terhadap suatu rancangan undang-undang, maka dapat dipastikan kemudian tidak akan pernah ada suatu rancangan undang-undang, yang selanjutnya dapat menjadi undang-undang. Selain itu, dalam ketentuan ayat (4) dari Pasal 20 UUD 1945 ditentukan pula, bahwa berkaitan dengan pengesahan rancangan undang-undang, untuk menjadi undang-undang dilakukan oleh Presiden. Seolah-olah ketentuan tersebut menegaskan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi Presiden, untuk kemudian mengesahkan rancangan undang-undang, yang merupakan hasil kerjasamanya dengan DPR dalam bentuk bakunya, yaitu persetujuan bersama, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Tujuan utama daripada pengesahan rancangan undang-undang, adalah untuk menjadikannya undang-undang, sehingga nantinya akan mengikat secara formil, dikarenakan sudah mendapatkan suatu pengesahan dari Presiden, dalam bentuk penandatanganan, disertai pula dengan suatu perintah tegas, untuk kemudian mengundangkannya dalam lembaran negara. Adanya pengundangan rancangan undang-undang bertujuan agar nantinya mengikat seluruh rakyat Indonesia, atau dengan kata lain undang-undang tersebut, selanjutnya akan mengikat umum, sehingga dapat dikenakan sanksi apabila dikemudian hari nanti ada yang melanggarnya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa jikalau rancangan undangundang sudah menjadi undang-undang, maka berlakulah asas hukum bahwa tidak ada maaf
I Gusti Ngurah Santika, SPd
507
ataupun alasan untuk mengatakan, bahwa bila melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut, kemudian menyatakan tidak tahu akan adanya undangundang tersebut. Tidak lain, dikarenakan dengan diundangkan dalam lembaran negara inilah, maka undang-undang untuk selanjutnya akan memiliki kekuatan mengikat dan bersifat memaksa. Bahkan, berkaitan dengan keberlakuannya kelak, ternyata dapat dipaksakan pula oleh alat perlengkapan negara, apabila memang dilanggar, walaupun nantinya bisa saja ada orang menyangkal norma tersebut, dengan alasan ketidaktahuannya akan adanya undang-undang tersebut. Hal mana merupakan suatu penerapan daripada teori fictie, hal mana teori tersebut menganggap semua orang sudah tahu akan adanya undangundang tersebut. Ternyata apa yang telah dikemukakan di atas adalah sama dengan pendapat, yang kemudian dinyatakan oleh Kansil dan Christine (2002;20) berkaitan dengan asas fictie, hal ini berarti bahwa jika ada seorang yang melanggar undang-undang tersebut, ia tidak dapat diperkenankan membela dan membebaskan diri dengan alasan: Saya tidak tahu menahu adanya undang-undang itu. Dengan demikian, ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 akan terlihat dengan jelas bahwa untuk menjadi undang-undang, maka rancangan undang-undang haruslah kemudian mendapatkan pengesahan dari Presiden. Jika pasal tersebut dicermati, maka selanjutnya akan dapat dimengerti, bahwa pada kenyataannya seakan-akan bunyi dari pasal tersebut, telah secara tidak langsung membedakan kedudukan dan tugas antara Presiden sebagai kepala negara, dengan Presiden yang bertugas sebagai kepala pemerintahan. Perbedaan tersebut akan lebih tampak, apabila kemudian kita mencoba untuk membandingkan pengertian, antara tugas Presiden dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 di bidang pemerintahan, terutama pada saat keterlibatan Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang sampai akhirnya mendapat persetujuan bersama untuk kemudian menjadi undang-undang. Sedangkan dilain pihak, terlihat tampak berbeda sekali dengan tugas Presiden sebagai kepala negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945, khususnya jika dinilai dari kekuatan mengikatnya rancangan undangundang, yang diharuskan mendapatkan pengesahan kembali dari Presiden. Dengan demikian, terlihat sepintas bahwa dalam sistem pemerintahan Presidensial, terdapat dua kepribadian hukum dalam organ yang sama (satu organ negara), yaitu Presiden, tentunya kebenaran pendapat penulis tersebut, adalah sangat tergantung dari praktek ketatanegaraan di lapangan nantinya. Dengan kata lain, penulis memahami kedua ayat tersebut dengan dua pengertian berbeda, hal mana tentunya ke depan sangat tergantung pula daripada praktek di lapangan ketatanegaraan nantinya. Bagaimanakah jika kemudian Presiden tidaklah menandatangani rancangan undang-undang yang sebelumnya sudah mendapatkan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
508
persetujuan bersama, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Tidak lain, dikarenakan tampak terlihat sedikit perbedaan maksud antara pengaturan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dengan ketentuan ayat (4) dari Pasal 20 UUD 1945. Pengertian tersenut tidak akan berbeda, jika dalam kenyataannya Presiden sebagaimana dimaksudkan ketentuan ayat (4) dari Pasal 20 UUD 1945, dalam menjalankan kewenangan tidaklah menolak untuk mengesahkan rancangan undang-undang agar menjadi undang-undang, hanya dengan menandatanganinya sebagaimana mestinya. Dikarenakan memang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama, antara Presiden dengan DPR dalam sidang paripurna. Walaupun dalam kenyataan sendiri di lapangan, bahwa dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, terdapat ketentuan yang memperkenankan Presiden untuk menugaskan pembantunya, yaitu menteri terkait guna mewakilinya dalam pembahasan bersama antara DPR dan Presiden, terutama dengan rancangan undang-undang yang akan disahkan oleh Presiden. Namun, jika dalam kenyataan Presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Maka praktek yang kemudian dianut, adalah secara jelas adanya pemisahan kedudukan dan kewenangan antara Presiden sebagai kepala pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2) dari Pasal 20 UUD 1945, dengan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945. Sehingga, andai kata nantinya Presiden betul-betul tidak menandatangani rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah mendapatkan presetujuan bersama tersebut, maka dalam hal ini akan terlihat jelas bahwa konsep yang dianut, adalah pola pembentukan undang-undang dalam sistem pemerintahan yang menganut parlementer. Dalam pada itu, berkaitan dengan pembentukan undang-undang dalam sistem parlementer, sudah ditentukan dengan jelas adanya pemisahan tegas, antara pembahasan rancangan undang-undang yang telah dibahas sebelumnya oleh menteri sebagai wakil pemerintahan, untuk selanjutnya disahkan kembali oleh raja, yang pada dasarnya berkedudukan sebagai kepala negara. Tampaknya dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945, selanjutnya berkaitan dengan pembentukan undang-undang dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945, ternyata MPR telah mengantisipasinya dengan membentuk ketentuan lain sehingga nantinya tidak timbul permasalahan terkait dengan adanya ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945. Adanya ketentuan lainnya tersebut, bertujuan agar semua rancangan undangundangan yang sudah mendapat persetujuan bersama, kemudian menjadi undang-undang dengan adanya ketentuan tambahan, yaitu ketentuan ayat (5) dari Pasal 20 UUD 1945. Dalam ketentuan ayat (5) dari Pasal 20 UUD 1945, telah pula ditegaskan, bahwa apabila
I Gusti Ngurah Santika, SPd
509
dikemudian hari Presiden, dalam kenyataannya tidak mengesahkan rancangan undangundang yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama, sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD, 1945, maka dalam kurun waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut, selanjutnya akan menjadi undang-undang secara otomatis, walaupun tanpa adanya pengesahan daripada Presiden, seperti apa yang ditentukan dalam ketentuan ayat (4) Pasal 20 UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan ini telah meneguhkan kembali komitmen Presiden, agar rancangan undang-undang yang sebelumnya telah disetujui bersama tersebut, sudah seharusnya disahkan untuk menjadi undang-undang. Ketentuan ayat (5) dari Pasal 20 UUD 1945 tersebut, telah memberikan suatu penilaian yang sifatnya luhur terhadap ketentuan ayat (2) dari Pasal 20 UUD 1945, terkait dengan adanya persetujuan bersama, hal mana tentunya mengikat Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang sebelumnya telah menyatakan kehendaknya, untuk selanjutnya menyetujui rancangan undang-undang tersebut bersama dengan DPR, sehingga menjadi undang-undang. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan jelas terlihat kemudian bahwa sebenarnya rancangan undang-undang, sudah dapat dipastikan menjadi undang-undang, apabila sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945). Walaupun sebenarnya rancangan undang-undang tersebut, kemudian telah ditentukan memerlukan pengesahan Presiden. Tetapi apabila pun dalam kenyataannya Presiden tidak mau menandatangani rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama, maka keberlakuannya hanyalah menunggu waktu saja, agar rancangan undang-undang tersebut, kemudian menjadi undang-undang serta mengikat rakyat, yang mana telah ditentukan secara tegas batas waktunya dalam UUD 1945, yaitu selama 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut mendapatkan persetujuan bersama. Namun, dengan hadirnya ketentuan ayat (5) dari Pasal 20 UUD 1945 tersebut, terkesan memperbolehkan Presiden, untuk tidak mengesahkan rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah mendapat persetujuan bersama. Berarti, nantinya akan ada suatu rancangan undang-undang, mungkin oleh suatu sebab yang tidak dapat diketahui, akhirnya suatu rancangan undang-undang berlaku mengikat umum, tanpa mendapatkan pengesahan dari Presiden. Dengan kata lain, adanya UU yang berlaku dengan tidak mendapatkan pengesahan formal, seperti sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan ayat 4 dari Pasal 20 UUD 1945, karena memang telah ditentukan batas waktu pemberlakuan rancangan undangundang, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama di mana hanya tinggal menunggu waktu berlaku secara otomatis, yaitu tidak lebih dari 30 hari setelah rancangan undang-undang tersebut mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
510
Selanjutnya dengan pendapat yang bernada sama juga dikemukakan oleh Isra (2010;228), pada dasarnya ia menyatakan bahwa bagaimanapun dengan hadirnya ketentuan Pasal 20 ayat (5), Presiden dapat menghindar dari kewajiban untuk menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR. Dengan demikian, ketentuan ayat (5) dari Pasal 20 UUD 1945 ternyata memberikan pembenaran konstitusional terhadap praktek parlementer dalam sistem pemerintahan presidensial, terutama di bidang pembentukan undang-undang. Atau dapat pula dikatakan, bahwa dengan adanya ketentuan ayat (5) dari Pasal 20 UUD 1945, telah memaksakan praktek parlementer dalam bidang pembentukan undang-undang, agar kemudian seoalah-olah terlihat, seperti pembentukan undang-undang dalam sistem pemerintahan yang menganut presidensial. Sesungguhnya kebenaran terhadap pendapat tersebut, adalah sangat tergantung kepada kehendak baik daripada Presiden sendiri, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan ini. Karena apabila Presiden menandatangani setiap rancangan undang-undang, yang sebelumnya memang telah mendapatkan persetujuan bersama, maka tentunya praktek yang kemudian terlihat adalah sistem pemerintahan presidensial dalam pembentukan undangundang, agar selanjutnya jangan sampai berlaku ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Sehingga, jika ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 berlaku, maka akan tampak terlihat seperti praktek pembentukan undang-undang dalam sistem pemerintahan yang menganut parlementer. Sudah seharusnya dengan adanya ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang secara jelas menyatakan, bahwa Presiden mengesahkan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Namun, dikarenakan ada kata untuk dalam bunyi pasal tersebut, maka sepintas lalu dipahami bahwa persetujuan bersama sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) dari Pasal 20 UUD 1945, belumlah bersifat final dan mengikat. Dengan adanya pengertian seperti itu, maka rancangan undang-undang diharuskan untuk mendapatkan pengesahan dari Presiden, agar selanjutnya memiliki daya laku. Dikarenakan tanpa adanya pengesahan dari Presiden, maka rancangan undang-undang tidak akan pernah dapat menjadi undang-undang, sehingga dapat berlaku dan mengikat umum. Karena untuk menjadi undang-undang, sebagaimana dipersyaratkan kemudian dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945, maka rancangan undang-undang dianggaplah perlu mendapatkan pengesahan dari Presiden. Konsekuensi yang dianut dalam ketentuan pasal ini adalah adanya pemisahan yang tegas antara tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan dan tugas Presiden sebagai kepala negara. Di sana pula akan tampak terlihat dengan jelas sekali, bahwa Presiden berkedudukan dan berfungsi sebagai kepala negara, dalam bidang pembentukan undang-undang. Tugas daripada Presiden sebagai kepala pemerintahan,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
511
sebagaimana dimaksudkan oleh penulis di atas, adalah pada saat adanya pembahasan rancangan undang-undang antara Presiden dengan DPR, yang kemudian sampai akhirnya mendapatkan persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945). Setelah itu, dalam perjalanannya ditegaskan dalam ketentuan ayat (4) dari Pasal 20 UUD 1945, bahwa jika Presiden di kemudian hari ternyata menolak untuk mengesahkan rancangan undangundang, di mana sebelumnya telah bahas dengan DPR, sampai pada akhirnya mendapatkan persetujuan bersama, maka dalam hal tersebut dapatlah kemudian dikatakan, bahwa kedudukan Presiden adalah sebagai kepala negara. Dikatakan demikian, tidak lain dikarenakan adanya perbedaan kehendak Presiden, baik pada saat terjadinya pembahasan bersama rancangan undang-undang, sampai akhirnya menjadi undang-undang, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama. Tentunya praktek demikian, tidaklah mungkin dapat dibenarkan, khususnya dalam sistem pemerintahan yang menganut presidensial, di mana pada dasarnya tidak memisahkan kedudukan dan fungsi antara Presiden sebagai kepala negara, maupun Presiden dalam kaitan fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Pembedaan yang menjadi penting, karena banyak negara yang memang menganut praktek yang memisahkan antara kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu, yaitu khususnya negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Namun, di lingkungan negara-negara yang menganut sistem presidensiil murni, memang tidak diperlukan pembedaan dan apabila pemisahan antara pengertian kepala negara dan kepala pemerintahan itu. Yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja (Asshiddiqie,2006;127). Kemudian jika dalam sistem presidensial sendiri, yang memang pada kenyataannya tidak memisahkan kedua jabatan tersebut, karena hanya dipegang oleh satu orang. Maka dengan konsekuensi demikian, seharusnya yang terjadi adalah penandatanganan atau pengesahan rancangan undang-undang menjadi undangundang adalah paralel. Berarti sudah seharusnya sesuai dengan kehendak Presiden pada saat melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut, yang sebelumnya memang telah memberikan persetujuan bersama, yaitu antara kedua lembaga negara tersebut. Sehingga, jika selanjutnya terkait dengan rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, tentunya dalam sistem pemerintahan yang menganut presidensial tidak ada alasan lagi bagi Presiden, untuk selanjutnya menyatakan penolakannya untuk mengesahkan rancangan undangundang, yang memang telah ia bahas sendiri sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, penulis kemudian berpendapat bahwa ketentuan ayat (4) dari Pasal 20 UUD 1945 tersebut, dapat dikatakan merupakan suatu ketentuan yang pada dasarnya bersifat imperatif, sehingga harus dilakukan oleh seorang Presiden. Untuk mencapai suatu kesimpulan bahwa
I Gusti Ngurah Santika, SPd
512
sistem pembentukan undang-undang, terutama terkait masalah pengesahan rancangan undang-undang, agar dapat kemudian dikatakan telah menganut sistem pemerintahan presidensial, maka untuk itu, tidak hanya membaca dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945, namun juga harus diikuti dengan membaca ayat sebelumnya, yaitu ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, setidaknya Presiden untuk pengesahan rancangan undang-undang, tidaklah memiliki alasan mendasar untuk mengelak, dengan tidak menandatangani rancangan undang-undang yang sebelumnya ia bahas sendiri walaupun dalam kenyataannya diwakili oleh menteri terkait. Dengan demikian Presiden tidak memiliki hak untuk menolak untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut, dengan tidak membubuhkan tanda tangannya, sebagai tanda penolakan Presiden untuk tidak mengundangkan rancangan undang-undang tersebut dalam lembaran negara. Bahkan, jika selanjutnya pengertian yang demikian diberikan kepada ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945, sudah seharusnya untuk itu tidaklah perlu lagi mencantumkan pengaturan tambahan, yaitu berupa ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Karena dengan adanya ketentuan tersebut, telah semakin memperkuat atau mendukung untuk kemudian menerapkan praktek parlementer, khususnya dalam pembentukan undang-undang, padahal sebenarnya sistem ketatanegaraan Indonesia yang dinginkan oleh UUD 1945 sesudah diamandemen adalah menganut sistem presidensial. Hal mana adalah sesuai dengan kesepakatan awal, dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yaitu semakin mempertegas sistem pemeritahan yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 haruslah kemudian ditafsirkan sebagai sistem pembentukan undang-undang dalam sistem pemerintahan presidensial. Dikarenakan, memang pada hakekatnya sistem ketatanegaraan Indonesia tidak lah menganut sistem pemerintahan parlementer, yang di dalamnya memisahkan antara Presiden dengan kedudukan dan fungsinya sebagai kepala negara, di samping perdana menteri yang berkedudukan dan berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Jika, penafsiran demikian dianut, maka tentunya Presiden tidak mempunyai alasan apapun, untuk kemudian tidak mengesahkan rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama, untuk akhirnya menjadi undang-undang. Dan apabila dalam kenyataannya Presiden benar-benar tidak menandatangani rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama tersebut, apakah sesungguhnya yang menjadi alasan utama agar dapat dibenarkan oleh UUD 1945. Karena pada dasarnya, perubahan terhadap UUD 1945 sendiri, dari awal mulanya hanya ingin menegaskan kembali prinsipprinsip sistem ketatanegaraan yang dianut UUD 1945 setelah diamandemen adalah sistem pemerintahan presidensial, yang tentunya juga meliputi bidang pembentukan undang-undang? Apakah dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
513
terjadinya peristiwa tersebut, tidak bertentangan dengan sumpah jabatannya sebagai seorang Presiden, yang sudah ditentukan dengan tegas untuk menjalankan UUD 1945 serta undang-undang, di samping peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut dengan seluruslurusnya. Bahkan tindakan Presiden tersebut menurut penulis, dengan mengutip pendapat Prodjodikoro (1984;1) merupakan perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden terutama adalah penggaran terhadap hukum konstitusi, bahkan merupakan pelanggaran yang dapat dikatagorikan bersifat berat. Sehingga dapatlah kemudian dikatakan, merupakan suatu jalan yang mungkin dapat digunakan oleh lembaga terkait, untuk selanjutnya meminta pertanggungjawabannya di bidang pemerintahan. Sebagai akhir kata, bahwa tidak ada alasan lagi bagi Presiden untuk kemudian tidak menandatangani rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama. Sehingga berarti bahwa rancangan undang-undang itu telah diperdebatkan antara DPR dan Pemerintah pada saat pembahasan sampai akhirnya mendapatkan persetujuan secara materiil dalam rapat paripurna DPR. Kesempatan Presiden untuk menolak rancangan undang-undang adalah terletak dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu pada saat pembahasan bersama antara DPR dan Presiden, untuk mencari suatu kesepakatan dalam bentuk persetujuan bersama. Namun, setelah rancangan undangundang yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama, tidak dapatlah kemudian ditolak lagi oleh Presiden dengan alasan apapun. Penulis berpendapat bahwa setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, khususnya jika kemudian kita dibandingkan antara sebelum adanya amandemen dengan sesudah amandemen terhadap UUD 1945, terutama yang ada kaitannya dengan pembentukan undang-undang. Maka, dapatlah dikatakan bahwa dalam hal pembentukan undang-undang antara DPR dan Pemerintah/Presiden lebih mendekati model legislasi dalam sistem pemerintahan parlementer. Berbeda dengan sebelum perubahan dalam ketentuan Pasal 20 UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan dari DPR, maka untuk itu penulis berpendapat, bahwa tidak akan pernah ada rancangan undang-undang, yang kemudian dapat menjadi undang-undang, kalau sebelumnya tidak ada persetujuan dari DPR. Artinya di sini, barulah dapat kemudian dikatakan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif yang bertugas untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, memang pada waktu itu, Presiden memiliki semacam hak untuk menolak terhadap rancangan undang-undang, meskipun dalam kenyataannya rancangan undang-undang tersebut sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari DPR (semacam hak veto). Namun, sebenarnya di sinilah terlihat keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang. Inilah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
514
akibatnya, bahwa apa yang sebelumnya menjadi konsepsi untuk mendasari Perubahan terhadap UUD 1945, khususnya dalam bidang pembentukan undang-undang, ternyata tidak sejalan dengan apa yang kemudian menjadi hasil perubahan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya MPR lebih cermat dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, khususnya dalam bidang pembentukan undang-undang, sehingga kemudian apa yang menjadi kesepakatan awal untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, tidak melenceng dengan apa yang menjadi hasil setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Hal itu dapat terjadi, dikarenakan pada pembahasan perubahan UUD 1945, tampak terlalu besarnya kepentingan-kepentingan politik, yang saling beradu agar dapat memenangkan kepentingannya, sehingga hasilnya memang masih jauh dari harapan. Selain itu, dengan tidak adanya pengesahan dari Presiden tentang pemberlakuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, meskipun untuk sekarang dengan adanya ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, yang pada dasarnya memberikan batas waktu untuk berlakunya RUU yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama jika kemudian tidak disahkan oleh Presiden. Ternyata belum juga dapat menjawab pertanyaan, siapakah yang selanjutnya akan mengundangkan rancangan undang-undang tersebut untuk akhirnya menjadi undang-undang? Dalam kelaziman selama ini yang bertugas, untuk mengundangkan rancangan undang-undang tersebut, adalah menteri yang ruang dan lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang perundang-undangan, hal mana dinyatakan oleh UU No.10 Tahun 2004, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Tetapi kemudian yang menjadi masalah selanjutnya, adalah apa hak seorang menteri yang merupakan seorang pembantu Presiden, untuk selanjutnya atas nama Presiden mengundangkan rancangan undang-undang, yang sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dari Presiden sendiri, yang pada dasarnya merupakan atasannya. Atau dengan kata lain, bahwa kedudukan seorang menteri merupakan pembantu Presiden, tentu seharusnya bertindak atas perintah Presiden, tetapi ternyata bertindak lain dari kehendak Presiden yang menunjuknya. Dengan demikian, terlihat lemahnya legitimasi yang dimiliki oleh menteri, berkenaan dengan tugasnya untuk mengundangkan rancangan undangundang, yang sebenarnya ditolak oleh Presiden, untuk kemudian disahkan menjadi undangundang. Hal tersebut di atas dapat terjadi, diakibatkan format undang-undang yang berkepala surat dan bersubyek Presiden Republik Indonesia, sehingga untuk itu memerlukan tanda tangan Presiden, yang mana dapat diterima sebelum adanya perubahan UUD 1945, dikarenakan dulu sebelum adanya perubahan terhadap UUD 1945 dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) telah ditegaskan bahwa yang bertugas untuk memegang kekuasaan membentuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
515
undang-undang adalah Presiden. Tetapi untuk sekarang seharusnya tidak lagi seperti di atas, hal ini dikarenakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang telah beralih pada DPR, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Sehingga, keharusan untuk mengubah format undang-undang menjadi suatu yang sebetulnya tidak bisa ditunda-tunda lagi, sehingga benar-benar DPR lah sebagai pemegang kekuasaan membentuk undangundang. Namun, setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945, ternyata format undangundang masih tetap berkepala surat, yaitu Presiden, sehingga berakibat pula bahwa setiap pemberlakuan rancangan undang-undang memerlukan pengesahan Presiden, untuk menjadi undang-undang. Adanya ketentuan tersebut, bahwa Presiden harus menandatangani setiap rancangan undang-undang menjadi undang-undang, adalah selaras dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945. Namun, dengan adanya ketentuan ayat (5) dari Pasal 20 UUD 1945 merupakan pembiaran secara konstitusional, terhadap tindakan Presiden untuk tidak mengesahkan rancangan undang-undang, yang sebelumnya telah disetujui bersama. Berdasarkan pemikiran demikian, maka diperlukanlah sebuah lembaga yang nantinya, akan bertugas untuk mengundangkan rancangan undang-undang yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama dalam lembaran negara, sehingga kemudian mengikat umum. Tentunya berkaitan dengan hal tersebut, yang diberi tugas untuk mengundangkan rancangan undang-undang adalah Menteri Hukum dan HAM, yang mempunyai kedudukan sebagai pembantu Presiden. Rancangan undang-undang yang kemudian disahkan oleh Presiden akan berbeda dengan undang-undang yang tidak mendapat pengesahan dari Presiden, dimanakah kemudian letak perbedaannya? Dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) (2) (3) dan (4) dari UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa : Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(kursif penulis). Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, perbedaan antara undang-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
516
undang yang berlaku karena mendapatkan pengesahan dari Presiden dengan undangundang yang berlaku karena tidak mendapatkan Presiden, yaitu bunyi daripada kalimat pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Hubungan Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Berkaitan dengan praktek ketatanegaraan Indonesia, terutama antara hubungan eksekutif dan legislatif dipandang perlu untuk dikemukakan di sini. Karena untuk sekarang, sedang hangat-hangatnya diwacanakan hubungan antara Presiden dengan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, tampak adanya hubungan kurang harmonis, antara lembaga kepresidenan dengan lembaga legislatif, yang kemudian ditandai dengan terjadi saling tarik menarik berkaitan dengan tugas dan kewenangan di antara kedua lembaga negara tersebut. Kekurang harmonisan tersebut tampak di dalam hubungan antara DPR dan Presiden, khususnya berkaitan dengan tugas dan kewenangan Presiden yang ditentukan, baik di dalam UUD 1945 maupun dalam undang-undang lainnya, jika saja nantinya tugas dan kewenangan Presiden tersebut bersentuhan atau memerlukan dukungan dari DPR, baik dalam bentuk pertimbangan maupun persetujuan. Dengan demikian, pola hubungan antara ekskutif dan legislatif yang dibangun oleh UUD 1945 setelah diamandemen, yaitu dengan mengadopsi mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antara kekuasaan Presiden di dalam setiap mengambil keputusannya, namun dalam kenyataannya lebih menitik beratkan pengambilan keputusan berada di tangan DPR. Pola hubungan antara Presiden dan DPR pada dasarnya adalah menganut sistem pemerintahan presidensial, sehingga secara yuridis sebenarnya kedudukan Presiden dan DPR adalah sama-sama kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana yang memang dikehendaki oleh UUD 1945. Namun, berdasarkan kenyataan yang terlihat, maka sepintas lalu gayanya seperti dalam sistem pemerintahan yang menganut parlementer. Hal tersebut terjadi, dikarenakan tidak kecilnya pengaruh politis daripada DPR, yang memang sering terlihat dalam praktek, bahkan mungkin dapat dikatakan telah mengalahkan ketentuan yuridis, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 (tentunya pengertian di sini adalah dalam arti luas). Pendapat tersebut dikemukakan, karena akan terlihat dengan jelas ketika DPR dalam memberikan pertimbangan politis yang diberikan kepada Presiden, sehingga pada akhirnya akan berimbas pula terhadap tugas Presiden secara yuridis. Hal ini tentunya adalah tidak sesuai dengan apa yang kemudian menjadi kesepakatan awal dalam melakukan perubahan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
517
terhadap UUD 1945 oleh MPR, yang pada waktu itu sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciriciri umum sistem presidensial (Asshiddiqie,2009;243). Mengapa dalam kesepakatan MPR tersebut terutama dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, khususnya tentang kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dianut, perlu disempurnakan kembali? Apakah selama ini sistem pemerintahan Presidensial yang dianut oleh UUD 1945 tidak murni, sehingga perlu kemudian untuk disempurnakan kembali? Tidak lain dikarenakan, bahwa sebelum Perubahan UUD 1945 adanya pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, di mana MPR ketika itu menurut beberapa pendapat ahli merupakan lembaga legislatif (parlemen). Dikatakan seperti itu, dikarenakan kewenangan MPR dalam membuat aturan yang bersifat mengatur dan mengikat, yaitu dalam membentuk UndangUndang Dasar/atau mengubah Undang-Undang Dasar. Tentunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, merupakan peraturan yang pada dasarnya mengikat secara umum/berlaku untuk umum, walaupun keberlakuaannya hanya dibatasi kemudian oleh wilayah hukum di mana tempat berlakunya Undang-Undang Dasar tersebut. Oleh karenanya, MPR dapatlah selanjutnya dikatakan, sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, MPR ternyata memiliki fungsi yang mirip dengan lembaga legislatif, karena ikut pula membuat peraturan tertentu yang bahkan juga mengikat umum. Di samping itu, MPR ternyata juga mengangkat dan memberhentikan Presiden dengan suara terbanyak, sehingga mirip seperti sistem pemerintahan parlementer. Ketentuan ini memiliki kemiripan di mana biasanya dalam sistem pemerintahan parlementer, perdana menteri berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang diangkat dan diberhentikan oleh parlemen, karena parlemenlah yang menjadi titik sentral daripada kekuasaan dalam sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya terkait dengan hal tersebut di atas, Mahmud MD (2001;93) menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial (kuasi presidensial atau kuasi parlementer). Alasannya ialah karena di dalam sistem pemerintahan di Indonesia meskipun Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden tetapi Presiden bertanggungjawab kepada MPR; sedangkan anggota DPR itu seluruhnya merupakan anggota MPRKarena Presiden bertanggungjawab kepada MPR, maka sebenarnya Presiden, secara tidak langsung, bertanggungjawab pula kepada DPR yang merupakan anggota MPR itu. Oleh karena itulah, kemudian adanya amandemen terhadap UUD 1945, khususnya berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan, perlulah untuk disempurnakan kemudian, agar selanjutnya benar-benar dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut sekarang adalah sistem presidensial murni.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
518
Namun, terkait masalah tersebut di atas, jika kemudian kita lihat kembali, baik dalam teori yang telah dihasilkan setelah Perubahan UUD 1945, ternyata sistem pemerintahan yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sistem presidensial murni. Mengingat selanjutnya akan terlihat jelas pula daripada ciri-ciri sistem presidensial dalam UUD 1945, seperti yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Selain itu, juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 UUD 1945, dengan menyatakan bahwa Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara, sedangkan dilain pihak telah ditentukan bahwa menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian untuk DPR sudah ditentukan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Adanya pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945), yang dilakukan terpisah dengan pemilihan umum bagi anggota DPR (Pasal 19 ayat (1) UUD 1945). Presiden tidaklah dapat membubarkan dan/atau membekukan DPR (Pasal 7C UUD 1945), di samping Presiden dan Wakil Presiden telah ditentukan untuk memegang jabatan selama lima tahun (Pasal 7 UUD 1945). Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan karena kebijakannya tidak disetujui oleh DPR, namun Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan melalui pranata impeachment (Pasal 7A dan 7B UUD 1945). Jika kemudian dicermati daripada pasal-pasal tersebut di atas, nampak bahwa garis-garis yang selanjutnya ditentukan dalam UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial murni. Namun, apa yang telah tertulis di dalam UUD 1945 selanjutnya perlu kembali untuk dilihat dengan keadaan sebenarnya dalam realitasnya, yang tentunya harus disaksikan sendiri dalam praktek kehidupan kenegaraan. Jika, ditonton baik dari televisi maupun di baca kemudian dalam koran-koran, di samping pula dapat ditemui dalam berbagai buku. Maka, banyak para ahli selanjutnya menyatakan bahwa sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial, namun dalam prakteknya ternyata bergaya parlementer. Apakah sebenarnya yang menyebabkan banyak ahli tatanegara kemudian untuk menyatakan bahwa Indonesia telah menganut sistem pemerintahan presidensial dengan gaya parlementer? Tidak patut untuk disalahkan jika dikatakan seperti itu, terkait dengan sistem pemerintahan yang telah dianut oleh Indonesia. Hal mana tidak lain disebabkan adanya perbedaan mendasar, antara apa yang tertulis dalam konstitusi, dengan apa yang kemudian dipraktekkan dalam kenyataan. Praktek yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, sedangkan bertolak belakang dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi, di mana konstitusi telah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
519
menentukan dengan tegas bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Oleh karena itu, dapatlah kemudian dikatakan bahwa Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial ala Indonesia memiliki gaya parlementer, dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang bersentuhan dengan DPR. Hal ini jelas terlihat sekali, bahwa praktek yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial namun gaya dalam pengambilan keputusannya adalah parlementer. Hal tersebut dikarenakan kelambanan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Presiden, apalagi jika keputusan tersebut melibatkan peranan DPR. Yang menjadi penyebab utama dari kelambanan Presiden tersebut, tidak lain dikarenakan kurangnya dukungan yang datang dari DPR dalam setiap pengambilan keputusan, menyebabkan Presiden kemudian harus berpikir keras untuk menyusun strategi, agar kebijakannya tersebut memperoleh dukungan dari DPR. Ketidakmampuan Presiden untuk berusaha mengambil hati DPR, menyebabkan Presiden dalam menjalankan tugasnya, tidak akan mampu menyelesaikannya dengan baik. Bahkan dalam berbagai kesempatan, ternyata bukan dukungan yang kemudian biasanya didapatkan oleh Presiden, melainkan perlawanan sukup sengit dari DPR. Sehingga untuk selanjutnya dapat dipastikan, bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden akan selalu terhambat oleh DPR. Peristiwa tersebut terjadi, disebabkan oleh sering terjadinya konflik antara Presiden dengan DPR, sebagai dua institusi berbeda yang masing-masing memiliki kedudukan dan fungsi berbeda, namun ditentukan memerlukan kerjasama erat untuk mencapai suatu tujuan, terutama yang berkenaan dengan tugas Presiden, namun ditentukan memerlukan dukungan dari DPR (political support). Karena tanpa adanya keterlibatan DPR dalam bentuk dukungan politiknya, maka tindakan yang diambil oleh Presiden, dapat dipastikan selalu mendapatkan kritikan tajam dari DPR. Bahkan, senantiasa tindakan-tindakan Presiden yang dikritik oleh DPR tersebut, khususnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, adalah terlalu berlebihan, di samping tidak realistis dan hanya mencari popularitas saja di mata rakyat. Dengan besarnya kekuasaan yang kemudian diberikan kepada lembaga legislatif (legislative heavy) dibandingkan Presiden dalam UUD 1945, maka UUD 1945 pada dasarnya telah menggariskan, bahwa untuk DPR ditentukan memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada Presiden. Sedangkan dilain pihak untuk Presiden yang memang sebelumnya ditentukan memiliki kekuasaan sangat besar, kemudian dikikis secara drastis setelah terjadinya perubahan pertama terhadap UUD 1945. Dengan adanya perubahan pertama terhadap UUD 1945, terutama terhadap kekuasaan Presiden, sehingga berakibat daripada berkurangnya kekuasaan Presiden untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, yang sebelumnya telah ditentukan merupakan titik sentral dalam pengendalian kekuasaan pemerintahan dalam negara. Dikarenakan telah ditentukan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
520
sebelumnya, bahwa Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, juga secara tidak langsung ditentukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Kemudian terbukti dengan pengalaman sejarah Indonesia, sejak ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai kemudian dengan adanya perubahan pertama terhadap UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999, terlihat jelas bahwa kekuasaan yang begitu besar melekat pada diri pribadi Presiden. Besarnya kekuasaan Presiden tersebut, telah menimbulkan malapetaka bagi kehidupan rakyat, bahkan telah mengekang kebebasan serta hak-hak rakyat utamanya berkaitan dengan hak asasinya. Untuk itu, dalam rangka menuju kehidupan yang lebih demokratis, yaitu untuk mencapai negara hukum demokratis (democtratische rechtsstaat), mungkin dapat dicapai hanya dengan cara mengembalikan kekuasaan legislatif kepada DPR, maka dipandang perlu untuk mengurangi kekuasaan Presiden yang sedemikian besar diberikan oleh UUD 1945. Namun, dengan berkurangnya kekuasaan Presiden dalam UUD 1945, tentu akan diikuti pula dengan meningkatnya kekuasaan DPR, terlihat kemudian terkait dengan peranan yang diberikan kepada DPR oleh UUD 1945. Sedemikian besarnya kekuasaan DPR yang diberikan oleh UUD 1945 setelah amandemen, secara tidak langsung telah menyebabkan bandul kekuasaan berayun dan mengarah ke lembaga legislatif. Sehingga tugas-tugas pemerintahan yang ditentukan merupakan objek pengawasan dari DPR, menjadi tidak berdaya, terutama untuk menghadapi pengawasan politik daripada DPR. Tampak beralihnya kekuasaan dari Presiden kepada DPR, bahkan kekuasaan yang sebelumnya merupakan kewenangan mutlak Presiden (prerogative) untuk mengambil keputusan ditentukan memerlukan keterlibatan DPR. Dengan demikian, telah menyebabkan sedikit tidaknya Presiden harus selalu mengadakan kompromi terlebih dahulu dengan DPR sebelum mengambil keputusan. Paling tidak kemudian Presiden harus membuka telinga lebar-lebar, untuk selalu mencoba untuk mendengarkan pertimbangan yang datang dari DPR. Tentunya, diharapkan selanjutnya, agar Presiden harus senantiasa untuk berdaya upaya dalam usahanya mengambil keputusan untuk selalu memperhatikan pertimbangan DPR, di samping dengan memperhitungkan kembali kekuatan politik yang nantinya akan mendukung kebijakan Presiden. Sebab jika Presiden kemudian mencoba untuk tidak mendengarkan pertimbangan DPR, maka akan fatal akibatnya, terlebih lagi seperti sekarang ini telah ditentukan bahwa hampir seluruh tugas berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, dalam kenyataannya memerlukan bantuan berupa keterlibatan daripada DPR, baik dalam bentuk persetujuan maupun pertimbangan politis. Mungkin yang menjadi penyebab utama mengapa begitu besar kekuasaan yang diberikan kepada DPR oleh UUD 1945, yaitu dikarenakan adanya trauma masa lalu, di mana pada waktu itu kekuasaan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
521
Presiden terlalu dominan, telah berdampak pula terhadap ketidakmampuan wakil-wakil rakyat, dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan Presiden. Berdasarkan pengalaman tersebut di atas, maka pasca Perubahan Pertama UUD 1945 terkait dengan kekuasaan Presiden, telah terlihat bahwa kekuasaan Presiden menjadi begitu berkurang, bahkan tampak tidak berdaya untuk kemudian menghadapi kekuasaan DPR yang begitu besar, padahal kekuasaan DPR itu sendiri, baru diperolehnya dari hasil Perubahan Pertama UUD 1945. Pergeseran kekuasaan Presiden yang kemudian beralih ke DPR pada awalnya tentu disertai pula dengan harapan-harapan yang lebih baik, yaitu untuk mencapai kehidupan lebih demokratis. Dikarenakan berdasarkan pemikiran mendalam untuk menempatkan DPR dalam struktur ketatanegaraan dengan kekuasaan yang lebih besar daripada Presiden, dikarenakan pada dasarnya DPR terdiri dari wakil-wakil rakyat, maka secara tidak langsung, rakyat juga akan terjamin hak-haknya dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah, seperti yang terjadi pada masa lalu. Namun, efek negatif daripada berpindahnya kekuasaan Presiden ke DPR, tentunya juga tidak mungkin dapat dihindari, seperti adanya kelambatan pengambilan keputusan oleh Presiden, karena tidak mendapat dukungan politis dari DPR, padahal tugas Presiden tersebut sangat berat, seperti apa yang kemudian dibebankan oleh UUD 1945, khususnya dalam menyejahterakan rakyat. Dengan kekuasaan yang dimiliki sekarang, tentunya DPR memiliki kesempatan cukup untuk menghambat tugas-tugas Presiden dalam mencapai tujuan negara, seperti apa yang dibebankan pada pundaknya tersebut. Memang akan selalu ada efek negatif, jika tidak ada keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara, apalagi ingin menerapkan mekanisme checks and balances, yang adanya hanyalah saling mendominasi antara satu lembaga dengan negara lainnya. Apakah kemudian hal tersebut merupakan sepenuhnya kesalahan MPR yang telah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, sehingga telah menjadi penyebab berpindahnya kekuasaan Presiden kepada DPR, pada akhirnya Presiden tidak mampu untuk berbuat banyak dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraanya dengan baik? Penulis berpendapat bahwa kita tidak hanya dapat menyalahkan sepenuhnya hasil daripada perubahan terhadap UUD 1945, yang sebelumnya dilakukan oleh MPR. Pendapat tersebut dinyatakan, karena UUD 1945 itu sendiri pada dasarnya merupakan aturan yang bersifat mendasar, di dalamnya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya hal-hal yang diatur dalam konstitusi tersebut, hanya berupa garis-garis besar untuk selanjutnya dilaksanakan. Maka untuk itu, perlu dijabarkan kembali dalam bentuk peraturan yang kedudukannya lebih rendah, seperti undang-undang. Mungkin bisa jadi, penyebab utama daripada kegagalan Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, bukanlah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
522
disebabkan oleh diamandemennya UUD 1945, melainkan disebabkan oleh pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD 1945, seperti dalam bentuk undang-undang, sebagai peraturan yang kedudukannya tepat berada di bawah UUD 1945. Bisa saja kemudian pengaturan di bawah UUD 1945 itulah yang menyebabkan ketidakmampuan Presiden dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Tentunya biarpun sistem pemerintahan negara menganut presidensial yang jelas-jelas diatur dalam UUD 1945, namun dalam kenyataan jika kemudian tidak didukung oleh perangkat peraturan yang ada di bawahnya, dalam rangka untuk mendukung tegaknya sistem Presidensialisme. Maka tidak mustahil selanjutnya, akan menyebabkan sistem pemerintahan presidensial, yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut, kemudian berubah secara praktek ketatanegaraan. Minimal secara psikologis selanjutnya akan mengarah ke sana, peristiwa tersebut terjadi, dikarenakan oleh ketakutanketakutan yang kemudian dialami Presiden dalam bermitra dengan lembaga DPR sebagai lembaga politik. Untuk itu, hendaknya jangan sampai ke depannya undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan DPR, pada dasarnya merupakan peraturan yang berkedudukan di bawah UUD 1945, untuk pengaturan selanjutnya berkaitan dengan ketentuan UUD 1945, ternyata mengarahkan praktek pada sistem pemerintahan parlementer. Sebagai suatu negara demokrasi, di setiap negara tentunya akan terdapat suprastruktur dan infrastruktur, agar negara kemudian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Memang sudah baku, bahwa secara formal terlihat suprastrukturlah yang kemudian berwenang untuk mengambil keputusan dalam bidang kenegaraan. Namun kita tidak boleh lupa, bahwa kadang-kadang keputusan yang telah diambil oleh suprastruktur tersebut, ternyata sangat dipengaruhi oleh infrastruktur sebagai bagian daripada sistem struktur dalam kehidupan negara. Tentunya kemudian, dalam hal tersebut yang dimaksudkan adalah hubungan antara Presiden dan DPR sebagai suprastrukturd di satu pihak, selanjutnya partai politik sebagai infrastruktur yang mana di dalamnya termasukjuga tokoh-tokoh partai politik dipihak lain. Jadi dalam pengambilan keputusan, baik berkenaan dengan kewenangan Presiden yang ditentukan memerlukan kerjasama dengan DPR, maka mau tidak mau kita harus juga kembali melihat kedudukan partai politik sebagai salah satu aktor, yang dalam kenyataannya juga ikut terlibat untuk mengambil bagian penting dalam sistem pemerintahan apa yang selanjutnya akan dianut oleh suatu negara. Bahkan, partai politik erat sekali kaitannya dengan sistem ketatanegaraan, terutama dengan sistem pemerintahan yang kemudian akan dianut oleh suatu negara. Namun, terkadang masalah ini sering dilupakan orang, karena hanya berpikir secara yuridis saja, sehingga melupakan unsur politisnya. Padahal kedua hal tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena antara kedua masalah tersebut merupakan unsur yang sebetulnya saling mendukung, bahkan mempengaruhi satu sama lain
I Gusti Ngurah Santika, SPd
523
dalam sistem politik Indonesia. Partai politik memiliki arti yang penting dalam kehidupan ketatanegaraan di negara-negara demokratis, dikarenakan bahwa kedudukan partai politik tentunya sebagai kerangka utama untuk membentuk badan legislatif, yang lembaga legislatif sendiri merupakan salah sebagai simbol dari negara demokrasi. Dalam pengisian lembaga demokrasi (dalam hal ini adalah DPR) tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945, partai politik memainkan peranan utama. Selain itu, keterlibatan partai politik dalam pemilihan anggota yang kemudian akan duduk di dalam jabatan-jabatan publik terlihat jelas pula, seperti ditentukan dalam UUD 1945. Kemudian pernyataan tersebut terlihat sangat jelas dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang pada dasarnya mengamanatkan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dicalonkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Di lain pihak anggota DPR, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 ternyata dipilih melalui pemilihan umum, tetapi untuk selanjutnya yang dapat menjadi peserta dalam pemilihan umum (general election) DPR adalah partai politik (Pasal 22E ayat (3) UUD 1945). Ternyata untuk selanjutnya dapat mengetahui hubungan kelembagaan negara antara Presiden dan DPR, kita tidak mungkin hanya melihat ketentuan pasal-pasal yang telah ditentukan dalam UUD 1945, melainkan kita juga harus melihat kembali faktor politik, yang pada dasarnya menjadi latar belakang tidak harmonisnya hubungan antara Presiden dan DPR akhir-akhir ini. Dalam UUD 1945 terlihat secara garis besar bahwa kekuasaan DPR jauh lebih besar daripada Presiden, khususnya berkaitan dengan bidang pengawasan yang memang dimiliki oleh DPR, baik dalam bentuk pertimbangan maupun persetujuan. Namun, dengan besarnya kekuasaan DPR dalam bidang-bidang tertentu, dalam kenyataannya tidaklah kemudian dibarengi dengan adanya mekanisme untuk dapat menyederhanakan sistem kepartaian yang dianut oleh Indonesia. Karena setidaknya untuk mengurangi dampak negatif daripada besarnya kekuasaan DPR, adalah terletak pada sistem kepartaian yang perlu dirubah kembali. Di mana sistem kepartaian yang penulis anjurkan untuk Indonesia adalah sistem multi partai terbatas, namun pengertian terbatas tersebut adalah berhubung terjadi, karena disebabkan dengan pembatasan-pembatasan yang memang dapat dibenarkan oleh hukum. Pendapat tersebut dikemukakan, dikarenakan sebagai daya upaya untuk menyesuaikan sistem pemerintahan yang dianut sekarang, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, Presiden tidak terus menerus tersandera oleh partai politik terutama dalam pengambilan kebijakan, yang mana tentunya akan berlainan masalahnya dengan negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Namun Presiden dalam kenyataannya setiap mengambil suatu keputusan, apalagi keputusan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
524
tersebut bersentuhan dengan DPR, baik dalam bentuk pertimbangan maupun dengan persetujuannya, tentunya akan menyebabkan Presiden terlihat sedikit lebih lamban, karena akan selalu berpikir tentang bagaimana caranya agar keputusan yang kemudian akan diambil tidak mendapatkan kritikan pedas dari DPR. Seperti yang terlihat sekarang ini, dengan banyaknya jumlah partai politik disertai pula dengan kewenangan yang begitu besar diberikan oleh UUD 1945 kepada lembaga politik, yaitu DPR, telah menyebabkan kesulitan-kesulitan bagi Presiden dalam mengambil suatu keputusan. Faktor tersebutlah yang kemudian akan menyebabkan Presiden untuk terus dan selalu mempertimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang ada dan mendukungnya di DPR. Dampaknya tersebut di atas, secara jelas dapat terlihat adalah adanya pembahasan berlarut-larut antara pemerintah dengan DPR, berkaitan dengan kebijakan yang sangat perlu diambil oleh Presiden. Namun, dilain pihak keterlibatan DPR dalam rangka mendukung kebijakan Presiden tersebut, merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Karena tanpa adanya persetujuan daripada DPR, maka kebijakan tersebut tentunya tidak mungkin dapat dijalankan oleh Presiden. Sehingga dengan demikian, yang kemudian menjadi sorotan utama, bahkan dianggap sebagai penyebab utama kegagalan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah Presiden, bukannya DPR. Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya kita mungkin tidak dapat menyalahkan sepenuhnya Presiden, yang sebetulnya dalam mengambil keputusan selalu terlihat lamban, dikarenakan sepanjang perjalanannya, Presiden selalu saja terhambat oleh masalah kurangnya dukungan politik dari DPR dalam mengambil keputusan. Bahkan, kadang kala Presiden yang juga merupakan lembaga politik, dikarenakan juga berasal dari kekuatan politik (karena dicalonkan oleh partai politik), ternyata tidak mampu untuk memanfaatkan kekuatan politik, terutama melalui partai politiknya yang ada di DPR. Hal tersebut bisa saja terjadi, dikarenakan terlalu kecilnya jumlah dukungan yang memang dimiliki oleh partai politik pendukung Presiden. Tentunya faktor tersebut, akan menyebabkan kemandulan bagi jalannya pemerintahan, yang dipimpin oleh Presiden dikarenakan terhambat oleh masalah-masalah politis, yang sebenarnya jika dilihat secara proporsional hanyalah merupakan masalah, yang bisa dibilang sederhana. Sayangnya, sangat jelas terlihat bahwa ketidakmampuan Presiden dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan oleh adanya kerancuan, terutama dalam pembagian kekuatan politik yang diraihnya pada saat pemilihan umum, konkretnya dalam perolehan kursi partai politik yang mendukung Presiden. Sehingga untuk mendapat jawaban yang lebih tepat, adalah dengan jalan kita kembali menapaki proses politik, terutama pada saat pemilihan umum, dimana tidak adanya perolehan suara rakyat mayoritas di tangan satu partai politik, terutama partai politik pendukung pemerintah. Semua itu bisa saja terjadi, dikarenakan terlalu banyaknya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
525
partai politik sebelumnya menjadi kontestan dalam pemilu legislatif. Akhirnya menyebabkan terpolarisasinya kekuatan politik menjadi beberapa bagian, yang tentunya memiliki ideologi berbeda-beda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Dengan demikian, tanpa adanya dukungan politik yang jelas terhadap Presiden, tentunya kemudian akan tampak terlihat pula, terhadap kaburnya tanggung jawab atas kegagalan jalannya pemerintahan. Semestinya kegagalan jalannya pemerintahan yang disebabkan oleh masalah-masalah politis, pada dasarnya masalah tersebut berada di luar tugas pemerintahan. Maka, selanjutnya di hadapan mata rakyat seakan-akan terlihat bahwa Presiden lah yang dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bersalah atas kegagalan tersebut. Untuk itu, dapatlah penulis katakan bahwa ketidakjelasan pembagian kekuatan politik antara Presiden dan DPR, berkaitan dengan pelaksanaan tugas Presiden, akan menyebabkan kekurang mampuan Presiden untuk kemudian mengelola lembaga kepresidenan yang begitu besarnya. Sudah semestinya dalam sistem pemerintahan Presidensial, di mana adanya pemisahan yang jelas antara kedudukan dan fungsi lembaga legislatif dengan eksekutif, maka akan diharapkan dapat mempertegas tugas masing-masing lembaga negara tersebut. Sehingga dikemudian hari, tidak akan terjadi kerancuan antara tugas Presiden sebagai lembaga eksekutif sebagai memegang kekuasaan pemerintahan, dengan tugas DPR sebagai lembaga legislatif, bertugas untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang, yang disertai pula dengan hak-hak konstitusionalnya, terutama dalam bidang pengawasan. Karena sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah kekuasaan pemisahan (separation of power) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tentunya kemudian dalam menjalankan tugasnya, Presiden tidak perlu lagi ragu-ragu untuk mengambil keputusan, dikarenakan sebenarnya meskipun tanpa adanya dukungan dari DPR pun, sebenarnya Presiden dapat berjalan sendiri, tanpa takut akan dijatuhkan oleh DPR. Namun, terkait dengan pemaparan tersebut di atas adalah sesuai dengan pendapat dari Thoha (2011;36), pada dasarnya ia menyatakan bahwa ada juga yang mengikuti demokrasi presidensial akan tetapi peranan parlemennya juga sangat menonjol seperti demokrasi parlementer. Karena memang dalam setiap negara yang menganut demokrasi sebagai konsepnya utama, maka tentunya dengan begitu diikuti pula besarnya fungsi parlemen yang diberikan oleh UUD 1945. Bahkan, selanjutnya disertai pula dengan sistem multipartai, ditambah kecilnya dukungan politik terhadap Presiden, telah menyebabkan sistem pemerintahan yang dianut, adalah presidensial namun dalam praktiknya memiliki gaya parlementer. Kekuasaan presiden pasca Perubahan UUD 1945, tidak lebih merupakan sistem pemerintahan presidensialisme yang memiliki gaya praktik parlementer. Di mana titik berat kekuasaan ada pada tangan DPR, sehingga banyak pakar menyatakan bahwa
I Gusti Ngurah Santika, SPd
526
dulunya sebelum perubahan UUD 1945 Indonesia menganut executive heavy, namun setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945 menjadi legislative heavy. Legislative heavy ditandai dengan banyak tugas yang seharusnya menjadi kewenangan mutlak Presiden sebagai kepala negara. Kemudian dinamakan dengan hak prerogatif, namun dalam kenyataannya setelah adanya Perubahan UUD 1945, tidaklah sepenuhnya menjadi hak Presiden. Dikarenakan, dalam melakukan hak prerogatifnya tersebut, Presiden sebagai kepala negara dalam kenyataan mendapatkan pengawasan dari DPR, baik lewat pemberian pertimbangan maupun dalam bentuk persetujuan. Hal mana pada dasarnya menyebabkan tidak leluasanya Presiden untuk mengambil suatu keputusan, dikarenakan kurangnya dukungan politik dari DPR untuk mendukung kebijaksanaan Presiden. Sehingga selanjutnya menyebabkan di setiap pengambilan keputusan kemudian menjadi berlarut-larut, seperti apa yang terjadi kemarin pada saat pemerintah berencana untuk menaikan harga BBM. Dengan kewenangan yang dimiliki DPR, khususnya dengan hak-haknya yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 20A UUD 1945. Maka, secara otomatis DPR sebenarnya memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam melakukan kontrol terhadap tindakan Presiden yang menjalankan fungsi pemerintahan, misalnya saja dalam masalah pengangkatan berbagai jabatan publik, ternyata ditentukan bahwa Presiden perlu mendapatkan pertimbangan maupun persetujuan dari DPR. Dalam pada itu, dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 10 sampai 15 UUD 1945 sebelum diamandemen, merupakan hak prerogative (mutlak) daripada kepala negara. Namun, dalam kenyataannya setelah UUD 1945 diamandemen, mendapatkan berbagai bentuk pembatasan dari lembagalembaga negara lainnya dalam mengambil keputusan. Tentunya kemudian yang menjadi dalih utama untuk ikut campurnya DPR dalam pengambilan keputusan oleh Presiden, adalah untuk menerapkan mekanisme checks and belances di antara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, pada hakekatnya setiap perubahan berkaitan dengan suatu fungsi kelembagaan negara, tentunya akan membawa efeknya tersendiri, seperti menguatnya peranan DPR terutama dalam bidang pengawasan, hal mana tentunya secara tidak langsung akan melemahkan fungsi lain DPR. Hal tersebut selanjutnya akan berakibat pula pada menurunnya fungsi lainnya daripada DPR yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, dikarenakan terlalu besarnya porsi yang diberikan oleh DPR di bidang pengawasan. Padahal kita tahu bersama bahwa selain fungsi pengawasan, DPR juga memiliki fungsi lainnya yang memang diberikan oleh UUD 1945, yaitu fungsi legislasi dan anggaran. Dengan demikian, keseimbangan dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut sangat diperlukan, sehingga nantinya apa yang sebelumnya menjadi tujuan utama dalam bidang pengawasan, bukan hanya untuk mengawasi pengangkatan pejabat publik saja, tetapi juga
I Gusti Ngurah Santika, SPd
527
mampu menjalankan fungsi utamanya, yaitu dalam bidang pembentukan undang-undang. Karena sesungguhnya yang merupakan tugas utama daripada sebuah badan legislatif, adalah berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Apalagi kita mengetahui bersama bahwa UUD 1945, telah menentukan besarnya peranan Presiden dalam bidang pembentukan undang-undang dewasa ini. Hal mana tentunya tidak sesuai dengan kewenangan utama atau harapan besar yang sudah diletakan dalam UUD 1945, khususnya kepada DPR, agar selanjutnya menjalankan ketiga fungsi tersebut secara berimbang. Bahkan dapatlah kemudian dikatakan bahwa di dalam negara konstitusional (constitutional state), tugas utama daripada DPR sebagai lembaga perwakilan adalah menjalankan fungsi legislasi, selanjutnya barulah diikuti kemudian dengan fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi pengawasan maupun representasi. Namun, terlihat bahwa dikarenakan terlalu menitik beratkan pada satu fungsi, yaitu pengawasan, maka DPR dapat saja kecolongan dalam menjalankan fungsi-fungsi lainnya, seperti dalam bidang pembentukan undang-undang. Sedangkan dilain pihak, dengan dominannya kekuasaan Presiden dalam bidang pembentukan undang-undang, pastinya akan menyebabkan pula suatu masalah besar. Karena dalam UUD 1945 telah ditentukan, bahwa Presiden selain ikut mengajukan, ternyata juga membahas sampai akhirnya menyetujui rancangan undang-undang, sehingga menjadi undang-undang. Dilain pihak kekhawatiran akan semakin bertambah saja dikarenakan Presiden telah ditentukan sebagai bagian daripada badan yang bertugas untuk ikut pula dalam membentuk undang-undang, ternyata juga ditentukan untuk melaksanakan undang-undang di lapangan. Dengan demikian, fenomena tersebut akan memiliki dampak yang cukup negatif, karena jika saja dua kekuasaan (fungsi) tersebut benar-benar didominasi oleh Presiden sebagai satu lembaga, maka dapat dipastikan akan berimplikasi luas terhadap kehidupan demokrasi yang baru saja dibangun. Semua itu dapat saja terjadi, dikarenakan bahwa kedua kekuasaan tersebut kemudian terlihat dalam praktek hanya didominasi oleh satu lembaga negara, yaitu Presiden. Oleh karena itu, tentu dengan adanya gejala seperti tersebut, akan menimbulkan sesuatu yang mungkin saja tidak kalah seriusnya, apabila kemudian dibandingkan dengan fungsi pengawasan yang memang dimiliki oleh DPR, terutama dalam pengangkatan pejabat publik. Karena sudah sangat jelas sekali ditentukan, bahwa selain kekuasaan dalam bidang pelaksanaan undang-undang, yang merupakan salah satu fungsi daripada pemerintahan menurut undang-undang dasar, tentunya juga Presiden ikut terlibat untuk membentuk undang-undang, di samping memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden, pastinya kemudian akan terdapat berbagai ragam kepentingan-kepentingan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
528
daripada Presiden, baik dalam rangka tujuan yang memang sesuai dengan hukum, maupun tujuan yang tentunya bisa saja berpotensi, bahkan sangat bertentangan dengan maksud awal daripada kelahiran undang-undang, yang sebenarnya melatarbelakangi kelahiran undangundang tersebut. Sehingga selanjutnya seolah-olah terlihat bahwa DPR, tidak mampu untuk mengemban amanat dari rakyat, terutama dalam bidang pembentukan undang-undang, yang nantinya akan mengikat mengatur dan rakyat. Sehingga tentunya sangat bertentangan pula dengan konsep negara, yang pada dasarnya menyatakan telah menganut negara demokrasi dengan mengutamakan sistem perwakilan. Dengan demikian, pertumbuhan demokrasi di negara-negara konstitusional modern menimbulkan paradox ini, yaitu semakin banyak volume undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif pilihan rakyat dan kebutuhan rakyat memang menghendaki hal itu, maka semakin besar wilayah kekuasaan eksekutif yang tidak terkontrol dalam pelaksanaan undang-undang yang dibuat dengan cara demikian (Strong,1966;319). Sehingga untuk itu diperlukan kontrol yang ketat di bidang pengawasan, terutama berkenaan dengan pembentukan undang-undang, kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam bidang pangawasan yang memang seharusnya dilaksanakan oleh DPR. Jika saja, pengawasan dalam fungsi pembentukan undangundang/legislasi ternyata tidak berjalan dengan baik, tentunya akan berakibat fatal terhadap kehidupan demokrasi. Seperti tersebut di atas, berulang kali pula dikatakan bahwa karena kedudukan pemerintah sebagai badan yang ikut terlibat dalam mengajukan rancangan undang-undang, di samping ditentukan untuk ikut membahasnya, bahkan termasuk juga memberikan persetujuan hingga akhirnya rancangan undang-undang tersebut benar-benar menjadi undang-undanng. Tentunya akan berpotensi untuk kemudian menjadikan pemerintahannya sebagai cabang utama yang mengatasi dan mampu memonopoli segalanya, karena pemerintah jugalah nantinya yang akan menjalankan undang-undang. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar benar-benar kemudian diseleksi lagi, berkaitan dengan jabatan-jabatan publik mana yang seharusnya mendapatkan persetujuan dari DPR, sehingga tugas utama yang memang diamanatkan oleh UUD 1945, tidaklah menjadi terbengkalai, oleh dikarenakan disibukannya DPR dalam rangka memberikan pertimbangan, persetujuan atau memilih pejabat-pejabat publik. Jangan sampai rakyat kemudian memberikan cap kepada lembaga ini, seperti pada waktu zaman Orde Baru berkuasa, DPR ketika itu dianggap tidak lebih sebagai rubber stamp. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Roosadijo (1982;35-36) dengan menyatakan bahwa tak heranlah apabila kemudian terhadap lembaga negara (DPR) ini, terlalu sering dikonstatasi lamban, kurang tanggap, tidak berwibawa dan lain sebagainya, baik dalam bidang pembentukan perundang-undangan, maupun sebagai alat kontrol (supervisor) terhadap setiap
I Gusti Ngurah Santika, SPd
529
kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bahkan, terlihat selanjutnya bahwa berkaitan dengan adanya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR, berkaitan dengan pengangkatan pejabat publik ternyata kurang membawa manfaat yang cukup besar. Jika kenyataan tersebut dilihat kemudian dari sudut profesionalisme diantara calon yang dipilih oleh DPR, karena pada dasarnya keikutsertaan DPR dalam pengangkatan pejabat-pejabat publik hanya berdasarkan pertimbangan politis semata. Dikarenakan sudah terbukti selama ini bahwa berkaitan dengan bentuk keikutsertaan DPR dalam rangka pengangkatan pejabatpejabat publik hanyalah dapat dipandang daripada prinsip-prinsip demokrasi, yang mana tentunya hanya mendasarkan diri pada legitimasi rakyat. Sehingga selanjutnya jika dilihat dari sudut pekerjaan, pola rekruitmen seharusnya menggunakan mekanisme birokrasi dengan menggunakan jenjang karir, sebagai prinsip utama daripada profesionalisme. Sedangkan dilain pihak, tampak terlihat pula dalam kenyataannya, berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan DPR dalam pengangkatan jabatan publik, tidak semata-mata didasari pada profesionalisme. Tidak heran apabila hal tersebut terjadi tidak lain disebabkan pengangkatan jabatan publik yang dilakukan DPR, lebih besar sifat politisnya, disebabkan DPR sendiri sebenarnya adalah sebuah lembaga politik. Jadi, semua keputusankeputusannya hanya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politiklah yang memang lebih menonjol bila dibandingkan dengan profesionalitas, yang sebenarnya pejabat birokrasi seharusnya lebih mementingkan kemampuan dalam mengemban jabatannya kelak, ketimbang hanya kemudian berdasarkan kepentingan-kepentingan politik, yang pada dasarnya bersifat sesaat dengan tujuan memberikan keuntungan kepada elit politik. Bahkan, banyak fakta yang menunjukan bahwa anggota DPR dalam melakukan pengangkatan jabatan-jabatan publik tertentu, dikemudian hari ternyata setelah itu tersandung berbagai kasus, seperti adanya kasus penyuapan, tindakan tersebut terjadi dikarenakan calon yang ingin terpilih untuk menduduki jabatan publik dalam kenyataannya melakukan berbagai tindakan politis, seperti melobi anggota DPR agar dipilih bahkan dengan janji-janji akan memberikan keuntungan tertentu. Sehingga disinilah terlihat kelemahan daripada DPR dalam pengangkatan pejabat publik, yang untuk itu perlu dipikirkan kembali, bahkan dapat saja ditinjau ulang. Dilain pihak menurut penulis, beberapa kewenangan DPR dalam pengangkatan pejabat-pejabat publik baik melalui persetujuan maupun pertimbangan, perlulah pula untuk diberikan kesempatan kepada lembaga negara lainnya, seperti DPD yang memang selama ini hanya memiliki satu tugas saja, khususnya dalam pengangkatan pejabat publik, seperti adanya pengangkatan anggota BPK. Bahkan keterlibatannya dalam proses pengangkatan anggota BPK, DPD ditentukan hanya berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada DPR. Jadi, dengan diberikannya beberapa kewenangan dalam bidang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
530
pengangkatan pejabat publik kepada DPD oleh DPR, tentunya ke depan diharapkan DPR dapat berkonsentrasi terhadap tugas dan wewenangnya, terutama berkaitan dengan fungsi utamanya dalam UUD 1945 seperti legislasi, pengawasan dan anggaran, selain itu tentunya juga menjalankan fungsi representasi sebagai wakil rakyat. Intinya pendapat tersebut kemudian akan lebih meringankan tugas-tugas daripada DPR untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional yang memang diembankan oleh UUD 1945. Sistem Pemerintahan Presidensialisme Menurut UUD 1945. Lebih lanjut terkait dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945, sekarang telah berkembang wacana luas dikalangan para ahli, berkaitan dengan lembaga kepresidenan yang ternyata tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Di lembaga kepresidenan bertahan dengan sistem presidensil, tetapi semangat yang berkembang di lembaga legislatif menuju ke arah sistem parlementer. Perubahan sistem pemilihan Presiden secara langsung adalah konsekuensi sistem presidensil, sedangkan sistem pembentukan kabinet, pengawasan dan pertanggungjawaban kebijakan politik cenderung ke sistem parlementer (Wiyanto,2010;214). Nampaknya, apa yang telah dinyatakan Wiyanto memang benar sekali untuk memberikan gambaran berkaitan dengan pembentukan kabinet. Dikarenakan dalam pembentukan kabinet sendiri, jika kemudian dilihat dalam UUD 1945, sebenarnya telah ditentukan dengan tegas, bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945). Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri tidak lain dikarenakan, bahwa menteri-menteri itu adalah pembantu Presiden (lihat Pasal 17 ayat (1) UUD 1945). Dengan konstruksi yuridis demikian, maka terlihat dengan jelas bahwa konsep yang mendasari dalam pembentukan kabinet adalah dengan mengutamakan hak prerogatif Presiden untuk kemudian menentukan, siapa yang seharusnya pantas untuk selanjutnya diangkat sebagai pembantunya kelak untuk menduduki kursi menteri di kabinet yang akan dibentuknya. Namun, jika kita lihat kembali dalam praktek tentunya berkaitan dengan hak Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, Presiden dalam kenyataannya tidak dapat dengan seenaknya menggunakan hak prerogatifnya, khususnya dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri. Setidaknya, secara politis untuk pengangkatan menteri-menteri tersebut, Presiden selanjutnya perlu melihat kembali kekuatan politik yang dimilikinya dan tentunya benar-benar mendukungnya, terutama partai politik yang mendapatkan kursi di badan legislatif. Oleh karena itu, Presiden seharus mencoba untuk kemudian kembali mengkalkulasikan semua kekuatan politik yang memang dimilikinya, termasuk dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
531
pengangkatan menteri ternyata perlu pula untuk memperhitungkan kekuatannya secara politis. Jika strategi tersebut tidak dilakukan Presiden, maka dapat dipastikan dalam perjalanannya selanjutnya akan terlihat terutama dalam jangka panjang, terhambatnya tugas Presiden oleh karena tidak diperhitungkannya kekuatan politik, pada saat membentuk formatur kabinet. Bahkan, terlihat kemudian dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bahwa berkaitan dengan pencalonan Presiden sendiri, ternyata ditentukan melalui jalur partai politik ataupun gabungan partai politik. Yang tentunya partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sudah ditentukan dengan jelas dalam undang-undang. Yang pertama, jika satu partai politik mampu untuk memenuhi semua persyaratan seperti sebagaimana dimaksudkan undang-undang, maka tentunya partai politik tersebut kemudian dapat untuk selanjutnya mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang kedua, jika dalam kenyataannya suatu partai politik tidak mampu secara mandiri untuk kemudian mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, maka telah ditentukan jalan keluar baginya agar bisa mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu telah tentukan suatu partai politik agar selanjutnya bergabung dengan partai politik yang lainnya, sehingga akhirnya mampu untuk memenuhi semua persyaratan dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, terkait dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik sebelum adanya pemilihan umum, tentunya sangat mempengaruhi pertimbangan daripada Presiden dalam membentuk formatur kabinet, terutama untuk selanjutnya menentukan pengangkatan orangorang yang pada akhirnya akan menjadi menteri di kabinetnya. Kesimpulan yang kemudian dapat diperoleh dari pembahasan di atas, bahwa terkait dengan pembentukan kabinet ataupun pengangkatan orang untuk menjadi menteri, tentunya sangat dipengaruhi dukungan dari partai politik sebelumnya, terutama dukungannya terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada saat sebelum adanya pemilihan umum sampai dengan terpilihnya calon tersebut menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jika dalam kenyataannya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari satu partai politik, tentunya tidak akan mengalami kesulitan bagi Presiden untuk selanjutnya mengangkat orang-orang yang memang dekat dengan partai politik Presiden, dikarenakan pada dasarnya partai politik yang mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut memang telah memenuhi syarat untuk kemudian mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun, bisa saja dikarenakan persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memang partai politik tersebut telah memenuhi syarat untuk selanjutnya mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun jika kemudian dilihat kembali dari perolehan kursi di DPR, ternyata partai politik tersebut
I Gusti Ngurah Santika, SPd
532
belum mampu menguasai mayoritas suara di parlemen, untuk selanjutnya menentukan kata akhir di setiap pengambilan keputusan yang memerlukan keterlibatan DPR. Karena sebenarnya Presiden dengan partai politiknya setidak-tidaknya haruslah mendapatkan dukungan, yang biasanya telah ditentukan sekurang-kurangnya 50 persen +1 anggota DPR. Namun, dengan melihat kondisi seperti sekarang ini, di mana jumlah partai yang ikut terlibat untuk berkompetisi dalam pemilihan umum legislatif adalah terlalu banyak. Akibatnya kemudian secara tidak langsung akan sangat berpengaruh pula terhadap perolehan suara partai politik tersebut, tentunya juga akan berpengaruh terhadap perolehan jumlah kursi akan yang didapatkan di parlemen oleh partai politik yang ikut terlibat untuk berkompetisi dalam pemilihan umum. Tentunya dapat dipastikan akan mengalami kesulitan suatu partai politik untuk kemudian mendapatkan suara mayoritas pemilih dalam pemilihan umum legislatif, karena dengan jumlah partai politik yang begitu banyaknya terlibat untuk berkompetisi dalam pemilihan umum (general election) tersebut. Jika dalam kenyataannya partai politik Presiden tidak mendapatkan kursi melebihi lima puluh persen jumlah suara dalam pemilu sebelumnya, maka jalan keluar yang perlu untuk diambil oleh Presiden, yaitu dengan mengadakan koalisi antara partai politik pendukung Presiden dengan partai politik lainnya yang juga mendapatkan kursi di parlemen, tujuan utamanya yaitu untuk memenuhi syarat agar suatu keputusan terkait dengan pemerintahan nantinya dapat diambil tanpa mendapat hambatan dari parlemen. Memang koalisi dapat saja menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau mungkin saja beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif (Soekanto,2009;68). Untuk mencapai tujuan partai politik pendukung daripada Presiden tersebut, yaitu meraih kursi mayoritas di parlemen, maka diperlukan gabungan antara partai politik yang duduk di DPR lewat koalisi. Sehingga nantinya dapat mencapai lebih dari setengah jumlah kursi di parlemen, agar selanjutnya lebih mudah bagi Presiden untuk mengambil keputusan, yang mana tentunya keputusan Presiden tersebut melibatkan DPR, lewat berbagai ragam pertimbangan maupun dalam bentuk persetujuan, baik yang sifatnya tidak mengikat maupun mengikat Presiden. Terkait dengan pengangkatan menteri, tentunya Presiden kemudian harus berusaha untuk selalu mendengar suara-suara dari partai politik-partai politik yang memang pada awal mendukungnya, terutama pada saat pemilu sebelumnya sampai kemudian dengan terpilihnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Semua hal tersebut tentu dikarenakan Presiden dan Wakil Presiden dalam kenyataannya dicalonkan oleh lebih daripada satu partai politik/gabungan partai politik. Namun, jika dalam kenyataannya Presiden berani
I Gusti Ngurah Santika, SPd
533
nekad untuk selanjutnya tidak mau mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari partai politik terkait dengan pengangkatan menteri. Khususnya pertimbangan yang kemudian datang dari partai politik pendukungnya, maka dapat dipastikan jalannya tugas kepresidenan ke depannya akan mengalami kesulitan yang berkepanjangan terutama jika berhadapan dengan DPR. Kesulitan akan datang kemudian, terutama dari partai politik yang pada dasarnya menentang dengan menunjukan sikap oposisi yang siap sedia untuk selalu menggagalkan setiap kebijakan Presiden agar nantinya tidak dapat direalisasikan. Jika lihat dengan cermat di sini, kemudian akan terjadi friksi antara Presiden disatu pihak dengan DPR di pihak lain, terutama yang datang dari pihak oposisi. Di sini kelihatan jelas bahwa pengangkatan menteri atau pemberhentian menteri dalam UUD 1945 merupakan kekuasaan mutlak (prerogative) Presiden, namun dalam menjalankan kewenangannya tersebut, terlihat Presiden bertindak untuk mengambil keputusan adalah dengan pertimbangan politis, yaitu berusaha untuk selalu memperhatikan kekuatan politik dari partai politik-partai politik yang mendukungnya. Semua hal tersebut bisa terjadi dikarenakan oleh resiko yang kemudian dibawa daripada sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai. Yang tentunya secara sadar mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa hak prerogatif Presiden akan terpengaruh oleh karena adanya sistem pemerintahan yang berdasarkan multipartai. Hal tersebut ternyata juga berimplikasi, terutama berkaitan tentang pengangkatan menteri, paling tidak pengaruh partai politik terhadap Presiden dalam proses pengangkatan menteri misalnya, untuk menentukan orangnya, sehingga Presiden kadang akan tersandera dalam dilema antara memilih orang yang menurutnya ahli atau mengikuti kehendak partai politik dengan menerima calon yang kemudian disodorkan tersebut, untuk selanjutnya diangkat sebagai menteri di kabinet yang dibentuknya. Jika kita analisis kembali, seperti apa yang pernah penulis kemukakan di atas, mandulnya kekuasaan Presiden ini diperparah lagi oleh sistem multi partai yang memang dianut oleh Indonesia. Memang partai politik dalam negara demokrasi merupakan unsur yang sangat penting, karena merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi. Untuk itu, mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa sebagai negara yang pada dasarnya mengaku untuk menganut sistem demokrasi konstitusional (constitutional democrazy), maka partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus ada. Partai politik sendiri merupakan suatu kelompok teroganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan programnya (Budiarjo,2008;403-404). Terlihat jelas dari pengertian tersebut bahwa suatu partai politik tentunya memiliki
I Gusti Ngurah Santika, SPd
534
orientasi, nilai-nila dan cita-cita yang sama, namun terkait hal tersebut hanyalah satu pengertian saja, yang terlihat hanya dari pengertian satu partai politik saja. Yang mungkin jika kita bandingkan kembali dengan partai politik lainnya, maka akan terlihat orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang mungkin akan berbeda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Tentunya adanya suatu perbedaan-perbedaan mendasar, merupakan salah satu sumber konflik, bahkan dipandang cukup potensial, yang tentunya sewaktu waktu bisa saja meledak, apabila kemudian berhadapan dengan satu sama lainnya. Hal ini hanya mungkin dapat dikurangi dengan semakin menyederhanakan jumlah partai politik, sehingga semakin mempersempit perbedaan-perbedaan yang ada, selanjutnya akan lebih mudah untuk kemudian menjadikannya lebih bersatu dalam menghadapi sebuah persoalan sama. Namun, dengan terlalu banyaknya partai politik yang mengikuti pemilihan umum, dengan berbekal orientasi, nilai dan kepentingan berbeda-beda, kemudian partai politik-partai politik ini akan memperoleh kursi di parlemen, sehingga menyebabkan perpecahan yang akhirnya berujung pada kegagalan partai politik dalam menyukseskan program pemerintahan. Dengan banyaknya partai politik yang ikut terlibat dalam pemilu, menyebabkan terpecahnya pembagian kursi di DPR, yang selanjutnya akan berimbas pula kepada dukungan Presiden, khususnya dukungan partai politik terhadap kebijakannya. Perpecahan tersebut terjadi, disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan pandangan yang memang dibawa oleh masing-masing partai politik tersebut, untuk diperjuangkan kembali menjadi sebuah kebijakan publik. Namun, jika diperhatikan dengan seksama dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, jelas bahwa seharusnya Pesiden memiliki kedudukan kuat karena telah ditentukan dan dipilih oleh rakyat secara langsung, bahkan disertai dengan persyaratan begitu besar berupa dukungan suara rakyat, yang sebenarnya menjadi sumber utama daripada legitimasi pemerintah untuk selanjutnya menjalankan kekuasaannya. Konsekuensi ini adalah dianutnya sistem pemerintahan presidensial, dengan adanya pembedaan pemilihan umum antara badan legislatif dengan eksekutif, atau pemilihan umum yang dilakukan terpisah antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta untuk pemilihan legislatif. Namun dalam ketentuan ayat (2) pasal dari Pasal 6A UUD 1945 tersebut, malahan terlihat memperlemah semangat dari ayat sebelumnya, yaitu pada ayat (1) dari ketentuan Pasal 6A UUD 1945. Hal ini karena ditentukan bahwa dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah ditentukan haruslah melalui partai politik atau gabungan partai politik, menyebabkan tertutupnya kemungkinan pencalonan perseorangan untuk kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, dengan banyaknya jumlah partai politik ikut terlibat untuk berkompetisi dalam kegiatan pemilu, telah menyebabkan terpecah-pecahnya pembagian suara rakyat yang tercermin dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
535
pembagian kursi di DPR, sehingga nantinya akan menyebabkan fragmentasi kekuatan politik ke dalam fraksi-fraksi kecil. Berpedoman kepada ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, maka merupakan konsekuensi logis untuk dianutnya sistem kepartaian yang multipartai, bahkan dengan besarnya kekuasaan DPR sebagai lembaga politik, hal mana ditentukan keanggotaannya diisi oleh partai politik, maka menyebabkan semakin tajamnya perbedaan kepentingan, yang kemudian berimbas pula terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, karena Presiden beserta partai politiknya harus melawan matian-matian partai politik oposisi yang ada di DPR. Sistem pemerintahan presidensialisme dengan multi partai sering menyebabkan kebuntuan dalam mengambil keputusan. Banyaknya partai menjadikan keputusan yang diambil menjadi berlarut-larut (Wibawanti,2009;24). Dikarenakan tidak adanya kesepahaman pandangan antara pemerintah disatu pihak dengan legislatif dipihak lain dalam menghadapi suatu masalah untuk kemudian memecahkannya. Dengan beratnya tugas Presiden seperti sekarang ini, ditambah dengan begitu ketatnya pengawasan yang selanjutnya dilakukan DPR, lebih berpotensi untuk menjadi penyebab kegagalan pemerintah dalam mengemban tugasnya seperti yang amanatkan oleh konstitusi. Di satu sisi DPR merupakan lembaga politik, ternyata hanya menjadi tempat bagi partai politik untuk merumuskan kepentingan-kepentingan politisnya dalam jangka pendek. Bahkan, bisa jadi partai politik menjadikan DPR hanya sebagai tangannya untuk kemudian memukul mundur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sistem multi partai telah membawa dampak yang cukup serius selama ini, jika kemudian kita cermati berkaitan dengan stabilitas politik pemerintahan yang ditimbulkannya, bahkan sistem multi partai cenderung mempertajam dan meruncingkan pertentangan yang ada. Dalam pada itu, menurut penulis masih jauh dari fungsi partai politik yang sebenarnya menjadi tugas utamanya, sebagaimana dimaksudkan kemudian oleh Budiardjo dalam Asshiddiqie (2006;159) bahwa partai politik seharusnya memiliki fungsi sebagai komunikasi politik, sosialisasi politik (political socialization), rekruitmen politik (political recruitmen), dan pengatur konflik (conflict management). Namun, untuk partai politik-partai politik di Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksudkan di atas, realitasnya kadang-kadang hanya menonjolkan sisi negatif dari keempat fungsi tersebut di atas. Padahal keempat fungsi ini harusnya dimiliki oleh partai politik untuk selanjutnya dilaksanakan. Namun, tentu yang tidak kalah pentingnya, diperlukan kehendak serta semangat yang jelas agar dapat kemudian menjalankan tugasnya, partai politik perlu selanjutnya melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dengan baik.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
536
Sistem multiparti memang membawa kelemahan tersendiri, terutama terhadap Presiden sebagai pemeran utama dalam pemerintahan presidensial, yang bertugas, untuk menjalankan pemerintahan, sehingga mampu menyejahterakan rakyat. Untuk itu, diperlukan cara yang dipandang tepat agar selanjutnya dapat mengurangi efek negatif yang nantinya muncul, disebabkan oleh sistem kepartaian yang dianut adalah multipartai. Bahkan memang beberapa jalan penah dicoba untuk bisa mengatasi hal tersebut, misalnya, dengan koalisi antara partai politik antara pendukung pemerintah, yang bertujuan untuk memperkuat barisan pemerintahan, terutama dalam menghadapi oposisi di DPR, walaupun sebenarnya koalisi yang dibentuk hanyalah koalisi pelangi. Dikatakan koalisi pelangi, dikarenakan partai politik yang ikut berpartisipasi berupa keterlibatanya untuk bergabung dalam koalisi adalah sangat banyak, bahkan dari berbagai aliran, maupun ideologi yang berbeda satu sama lainnya. Koalisi hanya dapat dilakukan ketika terjadi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan di antara partai-partai politik pendukung Presiden terpilih. Untuk dapat mengakomodasi pimpinan atau wakil dari partai-partai pendukung dalam pemerintahan maka Presiden perlu membuat struktur kebinet gemuk. Kombinasi ini diharapkan dapat memadukan pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil, sekaligus tingkat keterwakilan dalam parlemen yang tinggi (Monteiro,2009;55). Koalisi politik pasca pemilu merupakan satu keniscayaan yang harus terjadi di dalam sistem politik kita sekarang. Keperluan untuk berkoalisi tidak saja dilandasi oleh fakta politik yang terjadi, yakni tidak ada satupun partai politik yang mampu memperoleh suara mutlak karena sistem politiknya multipartai, namun juga didasari oleh keinginan politik yang kuat untuk melanggengkan kepentingan bersama (Urbaningrum,2004;163). Namun, apa yang kemudian dapat kita saksikan selama ini, bahwa yang menjadi daripada tujuan pada awalnya membentuk koalisi, ternyata belum sepenuhnya dapat diharapkan tercapai, seperti semakin kokohnya pemerintahan untuk selanjutnya berhadapan dengan partai politik yang menjadi oposisi di DPR. Hal mana semua itu terjadi, dikarenakan adanya ketidak konsistenan partai-partai politik yang ikut terlibat untuk membentuk koalisi, dalam mendukung kebijakan pemerintahan yang banyak bersinggungan dengan DPR. Partai-partai politik dalam koalisi ternyata masih mengkalkulasikan untuk kemudian mempertimbangkan untung dan rugi, atau popular dan tidak popular kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Apalagi untuk sekarang ini partai-partai politik yang terlibat untuk berkoalisi ternyata lebih memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh partai politiknya tersebut, apabila dikemudian hari mendukung atau tidak mendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan. Realitas tersebut sebenarnya telah menjadi semakin memperlemah daripada tujuan diadakan koalisi itu di antara partai-partai politik yang duduk di DPR, untuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
537
kemudian mendukung kebijkan Presiden. Kemudian jika lihat kembali antara apa yang menjadi antara realitas dengan idealitas adalah sangat ironis, karena sistem pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dengan dukungan yang dipersyaratkan begitu besar. Dukungan begitu besar dari rakyat kepada Presiden terpilih, namun dalam kenyataannya tidak seimbang dengan kekuasaan politik yang dimiliki Presiden dalam mengimbangi kekuatan DPR. Seperti yang kemudian dialami oleh SBY (Susilo Bambang Yudoyono) untuk kedua kalinya ia menjabat sebagai Presiden dengan dukungan rakyat 60 % suara rakyat, namun realitas dukungan kursi yang diperoleh partai politiknya di DPR hanya sekitar 20% ternyata telah menyebabkan lemahnya kekuasaan Presiden dalam bidang politik. Bahkan, sering terjadi konflik politik sendiri di antara barisan pendukung Presiden dalam koalisi, tentunya realitas tersebut telah menambah masalah yang pelik dalam perpolitikan di Indonesia. Sebenarnya untuk sejarah perjalanan sistem pemerintahan multipartai tidaklah asing dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang mana memang sudah pernah diuji cobakan pada waktu Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, dengan embel-embel demokrasi baratnya, namun ternyata dengan hasil yang tentunya saja bisa dibilang sangatlah mengecewakan. Berkaitan dengan sejarah sistem multi partai di Indonesia serta implikasinya, Marijan (1999;10) kemudian menyatakan bahwa sejarah masa lalu mengajarkan bahwa di antara faktor yang menyebabkan terjadinya konflik politik intens, yang sampai menimbulkan instabilitas politik adalah karena banyaknya partai politik. Tentunya, bangsa ini tidak menengok ke belakang terkait dengan sejarah multi partai yang dulunya pernah dianut, sampai kemudian mendatangkan kegagalan, karena adanya saling berebut kekuasaan untuk menjadi partai yang paling berpengaruh. Bahkan, dengan sibuknya berebut kekuasaan antara satu partai politik dengan partai politik yang lainnya, maka yang terlupakan adalah rakyat sendiri. Rakyat hanya bisa menonton perdebatan-perdebatan, intrik-intrik, tipu daya, antara partai politik satu dengan yang lain, karena rakyat hanya bisa menunggu kapan para elit politik tersebut berhenti sejenak, untuk selanjutnya memperdebatkan sedikit kepentingan rakyat kecil, seraya kemudian memperhatikan nasib mereka. Oleh karena itu, untuk ke depannya perlu dipikirkan kembali untuk kemudian menyederhanakan jumlah partai yang ada untuk selanjutnya dapat mengikuti pemilu. Implementasi pemikiran tersebut dapat dimulai dengan mencatumkan syarat-syarat yang sangat berat, untuk bisa mendirikan partai politik di dalam undang-undang. Dengan begitu sebenarnya juga akan berdampak positif terhadap kredibilitas daripada partai politik (political party) yang ikut terlibat untuk berkempetisi dalam pemilu. Rendahnya kredibilitas partai politik di mata rakyat, dikarenakan selama ini dengan banyaknya jumlah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
538
partai politik yang terlibat dalam koalisi, secara tidak langsung telah pula menyebabkan timbulnya suatu ketidakjelasan, antara siapa yang memegang kekuasaan, kemudian akan berimplikasi pada tidak jelasnya mengenai tanggungjawab partai politik dalam menjalankan pemerintahan kepada rakyat. Karena sebenarnya pertanggunjawaban tersebut, merupakan bentuk daripada akuntabilitas partai politik kepada konstituennya. Dengan adanya, ketidakjelasan mengenai siapakah yang memegang kekuasaan sebenarnya telah mengaburkan tanggungjawab partai politik, yang pada akhirnya menyebabkan saling lempar-melempar kesalahan, tanpa bisa mengambil suatu tindakan konkret untuk menyejahterakan rakyat. Dikatakan ada ketidak jelasan tanggungjawab partai politik di sini, dikarenakan memang tidak ada yang dapat memegang kekuasaan secara penuh antara partai politik tersebut. Hal mana tentunya kemudian didasari oleh sistem pemerintahan rapuh, yang dibangun di atas koalisi lemah, bahkan sewaktu-waktu dapat saja runtuh seketika, dikarenakan oleh adanya pertentangan kepentingan antar partai politik maupun di antara elit di dalam tubuh partai politik tersebut. Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan di atas, maka selanjutnya untuk di masa depan diperlukan suatu sarana, yang benar-benar mampu membatasi jumlah partai politik. Namun, perlu dicatat berkaitan dengan pembatasan tersebut tentunya tidak boleh dilakukan seperti pada zaman Orde lama dan Orde Baru, yaitu dengan melalui cara-cara yang dapat dipandang tidaklah demokratis. Niat baik ini, dapat dimulai dari political will DPR untuk membuat seperangkat undang-undang politik yang terkait dengan pengaturan di dalamnya terdapat syarat-syarat yang cukup berat, untuk kemudian dapat mendirikan partai politik. Bahkan ditentukan pula syarat bagi partai politik yang berhak, untuk selanjutnya mengikuti pemilu nantinya, kemudian dilanjutkan dengan batas perolehan kursi minimal yang diharuskan untuk didapat oleh partai politik yang bersangkutan di DPR, untuk selanjutnya dapat dinyatakan eksis dalam kelembagaan legislatif tersebut, sehingga untuk itu dapat membentuk fraksi. Misalnya saja dikemudian hari dengan menerapkan electoral threshold yang persentasenya dari waktu ke waktu semakin meningkat misalnya setiap 5 tahun. Dengan demikian, diharapkan akan dapat mengurangi partai politik yang ikut berkompetisi dalam pemilu, sehingga rakyat sendiri tidak pusing dalam memberikan suara kepada partai politik. Di mana sebelumnya dikarenakan terlalu banyak jumlah partai politik ikut terlibat untuk berkompetisi mengikuti pemilu, telah menyebabkan suara rakyat terpecah ke dalam partai-partai politik yang lainnya. Namun, dikarenakan electoral threshold hanya membatasi konstestan dalam pemilu, sehingga dirasa belumlah mampu secara efektif untuk mengurangi jumlah partai politik, dikarenakan persyaratan tersebut hanya menyangkut untuk keikutsertaannya dalam pemilu selanjutnya. Oleh karena itu,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
539
menurut penulis ada cara lain lagi yang berfungsi untuk selanjutnya dapat mengurangi dampak negatif daripada sistem pemerintahan multipartai seperti sekarang ini. Cara yang mungkin dapat untuk kemudian diterapkan, yaitu mengenai persentase jumlah kursi yang harus didapatkan partai politik di DPR untuk selanjutnya dinyatakan eksis di dalam lembaga legislatif tersebut yang pada akhirnya kemudian dapat mendirikan fraksi, hal mana biasanya disebut dengan nama parliamentary threshold. Untuk sekarang sedang digojlok oleh DPR terkait RUU tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang dalam isunya untuk kemudian semakin meningkatkan persentase parliamentary threshold, sehingga lebih mampu meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan. Namun, terkait dengan adanya parliamentary thershold ke depannya akan mendapatkan banyak kritik dan tantangan dari partai-partai politik kecil. Dikarenakan dengan besarnya terkait jumlah persentasi kursi di DPR yang dipersyaratkan untuk harus kemudian didapatkan partai politik, sehingga dapat dinyatakan suatu partai politik tersebut eksis di DPR untuk selanjutnya dapat membentuk sebuah fraksi tentunya akan menyebabkan partai-partai politik kecil tidak mampu untuk membentuk fraksi. Karena sudah dapat dipastikan bahwa kecilnya suara yang diperoleh partai politik tersebut, sehingga kemudian hanya akan mendapatkan kursi yang sedikit di DPR, bahkan dapat saja partai politik tersebut tidak cukup atau tidak mampu untuk membentuk fraksi. Bahkan, untuk sekarang ini menurut penulis, terkait dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR lebih baik natinya dihapuskan saja, dikarenakan dengan adanya fraksifraksi ini, ternyata dalam realitasnya telah menyebabkan DPR, terpecah belah menjadi beberapa kelompok kepentingan yang pada dasarnya memiliki berbagai perbedaan, baik idelogi serta program dari partai politik yang berbeda-beda. Dengan demikian keberadaan fraksi di DPR jelas bukan melayani kepentingan rakyat, namun hanya melayani kepentingan partai politik ataupun elit politik untuk kemudian memperjuangkan kepentingannya. Dengan demikian, lemahnya kekuasaan Presiden sekarang tidaklah sepenuhnya merupakan kesalahan dari adanya amandemen terhadap UUD 1945. Dikarenakan dalam realitasnya, pengaturan yang ada di bawah UUD 1945 ternyata tidak kecil peranannya, untuk kemudian mengatur dan memberikan arah untuk selanjutnya. Berdasarkan hal tersebutlah kemudian, kita tidak dapat begitu saja menyalahkan hasil daripada Perubahan UUD 1945 seluruhnya. Faktor utama yang menyebabkan, mungkin dikarenakan dalam legislatif, yang selanjutnya menjadi kekuatan utama lembaga ini adalah partai politik, namun jika dalam realitasnya kemudian ternyata undang-undang yang mengatur berkaitan dengan partai politik, seperti diamanatkan UUD 1945, telah membuka keran lebar-lebar, sehingga semakin mempermudah syarat-syarat untuk selanjutnya mendirikan partai politik,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
540
akan menyebabkan menjamurnya partai politik mendekati pemilihan umum. Kemudian dengan banyaknya jumlah partai politik yang ikut terlibat dalam berkompetisi untuk mengikuti pemilu, tentunya tidak akan ada satu partai politik, yang benar-benar mampu untuk menguasai kursi di parlemen. Sehingga pada akhirnya parlemen tersusun dari jumlah partai yang banyak. Dengan demikian, menyebabkan sistem presidensial dianut ysng disertai dengan sistem multipartai, telah menyebabkan kecil kemungkinan keberhasilan bagi Presiden dalam menjalankan kekuasaan. Hanya chile yang berhasil menjalankan sistem presidensial dengan sistem kepartaian, yang dianutnya adalah multipartai, namun tentunya hanya dengan menjalankan sistem pemerintahan otoriter. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer di mana jika terjadi ketegangan antara parlemen dengan pemerintah, maka pemerintah kemudian dapat saja membubarkan parlemen lewat keputusan raja/presiden, sehingga untuk selanjutnya mengadakan pemilihan umum secepatnya guna memilih anggota lembaga legislatif yang baru. Oleh karena itu penting untuk kemudian dipertimbangkan kembali, dengan mengurangi jumlah partai politik, yang disertai berbagai parsyaratan bahkan merupakan pembatasan konstitusional yang dipandang cukup berat. Implikasi multi partai tanpa pembatasan adalah inefisiennya pemerintahan dan terdistorsinya pemenuhan kesejahteraan rakyat (Wardhani,2009;84). Pertimbangan DPR Dalam Menerima Duta Negara Lain. Selanjutnya, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (3) UUD 1945 telah ditentukan, bahwa dalam hal penerimaan duta negara lain oleh Presiden, untuk itu perlulah kemudian mendapatkan pertimbangan dari DPR. Hal mana ketentuan tersebut menurut penulis adalah tidak sesuai dengan aturan yang lazimnya berlaku dalam hubungan internasional seperti sekarang ini. Adanya ketentuan inilah yang kemudian menyebabkan banyak negara-negara tetangga, mengeluh dalam pengiriman duta ke negara Indonesia. Disebabkan adanya berbagai pertimbangan-pertimbangan politik dari DPR, sehingga dalam realitasnya pertimbangan tersebut hanyalah menjadi penghambat utama tugas daripada Presiden untuk kemudian mengambil keputusan, hal mana keputusan tersebut tentu seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan dunia internasional. Mestinya, perlu untuk mendapat perhatian bahwa tugas-tugas kenegaraan yang dilaksanakan oleh Presiden dalam hal tersebut, adalah kewenangan Presiden untuk menjalankan hubungan yang baik antara negara satu dengan negara lainnya dalam pergaulan internasional. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, misalkan nantinya DPR, dalam memberikan pertimbangannya menyatakan, bahwa duta suatu negara lain yang dikirim ke Indonesia, pernah melakukan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
541
suatu perbuatan yang mungkin dipandang menurut ukuran DPR, bahwa merupakan suatu tindakan yang dapat dikatagorikan tidak patut di negaranya, apakah entah karena duta yang dikirim tersebut pernah melakukan pelanggaran hukum, baik itu korupsi atau tindakan lainnya yang bersifat melawan hukum. Apakah kita memiliki hak untuk menilai suatu perbuatan duta negara lain yang dikirim ke Indonesia? Tentunya kita tidak mungkin dapat mengukur perbuatan mereka, hanya dengan memandangnya dari sudut pandang Indonesia. Karena dalam menjalani hubungan internasional, yang menjadi konsep utamanya adalah tidak saling mencampuri urusan negara lain, termasuk tentunya kebebasan suatu negara untuk mengirim dutanya ke Indonesia. Bahkan, jika pada suatu saat pun, dalam kenyataanya duta negara lain yang ditugaskan di Indonesia tersebut, telah melakukan tindakan yang kemudian dapat digolongkan sebagai kejahatan (onrechtmatigedad or unlaw), yang pada dasarnya merupakan delik serta dapat dikatagorikan ke dalam hukum pidana di Indonesia (seperti dalam KUHP atau Wetboek van strafrecht or Criminal law). Apakah kemudian dalam hal ini duta negara tersebut dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Karena setahu penulis, bahwa dalam bidang hukum termasuk dalam hukum pidana ternyata untuk Indonesia menganut prinsip teritorialitas, yang pada dasarnya prinsip ini menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, bagi siapapun yang kemudian melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia atau di bawah kedaulatan Indonesia. Pernyataan tersebut sangat tegas tercantum kemudian dalam ketentuan Pasal 2 KUHP. Tentunya, menurut penulis bagi mereka yang bertugas sebagai seorang duta negara, tidaklah kemudian dapat dihukum dengan segala macam hukum Indonesia. Karena memang telah ditentukan seorang duta negara memiliki hak-hak, yang pada dasarnya hak tersebut dijamin oleh hukum internasional, yang di dalam ketentuannya tersebut mengatur juga tata cara mengenai pergaulan dalam dunia internasional berkaitan dengan perlakuan terhadap duta negara lain. Hak-hak sebagaimana dimaksud di atas, yaitu hak berupa kekebalan hukum sebagaimana dimaksud penulis, yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama hak imunitas di negara penerima duta tersebut bertugas. Tidak lain dikarenakan bahwa mengenai wilayah tempat duta negara tersebut bertugas, untuk mewakili kepentingan negaranya sendiri ditempat negara lain, dalam kenyataannya dianggap bukan lagi wilayah negara tempat duta tersebut sebenarnya berada. Kekebalan duta sebagaimana disebutkan sebelumnya ternyata mencakup Inviolability dan Immunity. Dalam pada itu, menurut pendapat dari Widagdo dan Whidiyanti (2008;100) bahwa inviolability diartikan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, sehingga di sini terkandung pengertian memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari
I Gusti Ngurah Santika, SPd
542
alat-alat kekuasaan negara penerima. Sementara Immunity diartikan sebagai kekebalan terhadap yuridiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Bahkan, berlakunya hukum pidana Indonesia ternyata dibatasi dengan berbagai perkecualian yang memang pada dasarnya diakui dalam hukum publik internasional. Pembatasan sebagaimana dimaksud tersebut di atas yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa rumah dan pekarangan dari para duta besar dan duta negara asing dianggap wilayah dari negara asing yang bersangkutan; 2. Bahwa para diplomat asing tidak dapat dituntut dimuka pengadilan dari negara tempat mereka ditugasi; 3. Bahwa kapal-kapal perang dari negara asing yang berlabuh di pelabuhan dalam negeri juga dianggap sebagai wilayah negara asing yang bersangkutan (Prodjodikoro,2008;58, bandingkan dengan (Moljatno,2008; 55). Sebagaimana telah diketahui selanjutnya bahwa perutusan-perutusan diplomatik menikmati pengecualian dari yuridiksi perdata dan pidana setempat. Perutusan-perutusan diplomatik juga tidak dapat diganggu-gugat diri pribadinya. Hak ini melindungi mereka dari penangkapan atau penahanan oleh penguasa setempat (lihat Pasal 25 Konvensi Wina) (Starke,2008;567). Bahkan, tidak hanya kemudian dalam hukum pidana saja, yang tidak mungkin dapat untuk menjangkau duta negara lain sebagai salah satu subyeknya. Ternyata dalam hukum pajak pun duta negara lain tidak termasuk subyeknya pula. Kalau kita melihat dalam ketentuan undang-undang tentang pajak penghasilan, yaitu UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000, dalam ketentuan Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa kedudukan atau tempat tinggal di Indonesia yang tidak dikenakan pajak adalah sebagai berikut. a. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, dan pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. b. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan. c. Perusahaan jawatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Dengan demikian, apa yang sebenarnya menjadi dasar daripada pertimbangan yang akan diberikan nantinya oleh DPR kepada Presiden, terkait dengan penerimaan duta negara
I Gusti Ngurah Santika, SPd
543
lain untuk Indonesia? Karena disatu pihak hukum internasional pun telah menjamin keberadaan duta negara lain, untuk melakukan tugas dan kewajibannya di negara tempat penerima duta tersebut. Sehingga tentunya berbagai alasan yang nantinya akan diberikan DPR kepada Presiden, seharusnya tidak akan berpengaruh. Terutama karena tidak mungkin dapat menolak menerima duta negara lain, apalagi hanya dikarenakan oleh adanya suatu pertimbangan dari DPR, yang tentunya dilengkapi dengan berbagai alasan-alasan politisnya. Karena hal tersebut sebenarnya memang berada di luar jangkauan kekuasaan daripada DPR, untuk menjalankan tugas pengawasannya. Karena dapat dikatakan bahwa sebenarnya merupakan hak negara lain untuk kemudian mengirimkan duta negaranya ke Indonesia, sebagai bagian daripada hubungan diplomasinya dengan negara penerima. Penulis bukan bermaksud untuk merendahkan pertimbangan daripada DPR kepada Presiden, terkait dengan penerimaan duta negara lain yang ditentukan oleh UUD 1945 memerlukan pertimbangan DPR. Namun, memang dalam kenyataannya pertimbangan yang diberikan tersebut sebenarnya tidaklah perlu, apalagi kemudian dalam kenyataannya pertimbangan yang diberikan tersebut, sampai benar-benar mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain dalam pergaulan internasional. Untuk itu, penulis menyarankan terkait dengan adanya pertimbangan DPR tersebut, agar tidak terlalu mempengaruhi sikap Presiden, dalam mempertimbangkan apakah akan menerima atau tidak terkait dengan duta negara lain, yang sedianya akan bertugas di Indonesia. Bahkan, jikalau dilihat dari sudut hukum pun, sebenarnya pertimbangan yang memang diberikan kepada Presiden oleh DPR, berkaitan dengan penerimaan duta negara lain, tidaklah memiliki kekuatan untuk mengikat Presiden guna menolak duta negara lain yang telah dikirim ke Indonesia. Namun, sebagai pemecahan masalahnya sekarang adalah merupakan suatu hak DPR, untuk kemudian mengetahui bahwa akan adanya duta negara lain yang dikirimkan ke Indonesia, untuk itulah kemudian DPR berhak mengetahuinya. Atau Presiden hanya memberikan konfirmasi semata kepada DPR. Pemberian Amnesti dan Abolisi Menurut UUD 1945. Sementara, terkait dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 bahwa DPR bertugas untuk selanjutnya memberikan pertimbangan politik kepada Presiden terutama berkaitan dengan adanya pemberian amnesti dan abolisi, menurut penulis adalah kurang tepat. Hal mana dikarenakan dalam pemberian amnesti dan abolisi tidak selalu terkait dengan tindak pidana politik. Kalau pun perlu, maka seharusnya Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan. Hal ini dikarenakan bahwa DPR merupakan badan politik,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
544
sedangkan yang diperlukan adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan politik, kemanusiaan, sosial, dan lain-lain, merupakan isi hak prerogatif (Manan dalam Huda,2011). Hal yang sebenarnya diperlukan untuk itu adalah pertimbangan hukum untuk memberi dasar yuridis bagi pertimbangan Presiden. Sehingga pertimbangan-pertimbangan DPR yang kemudian akan diambil oleh Presiden selanjutnya adalah pertimbangan hukum. Namun, terlihat jelas dalam sistem pemerintahan presidensialisme seperti yang terjadi di Indonesia, ternyata kebanyakan pertimbangannya yang diambil hanya berdasarkan faktor politis, seperti yang biasa terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer saja. Fenomena ini terjadi tidak terlepas dari masa lalu, di mana pada waktu itu besarnya kekuasaan Soeharto, dengan sistem pemerintahan presidensialisme, yang sebenarnya menjadi dasar utama kuatnya kekuasaan Presiden, sehingga tidak lembaga negara lainnya yang dapat melakukan pengawasan terhadap kekuasaannya.. Kondisi tersebut pada gilirannya menumbuhkan semangat anti-presidensialisme di kalangan anggota DPR pada masa reformasi. Sebaliknya sikap parlementarisme berkembang kuat, sebagai akibat banyak anggota DPR yang juga mengalami bagaimana sosialisasi politik Orde Baru dijalankan. Begitu kuatnya kekuasaan DPR sehingga semua pengangkatan duta besar sampai persoalan penjatuhan tidak langsung Presiden (Mufid,2007;116). Bahkan dapatlah kemudian dikatakan bahwa berkaitan dengan kekuasaan Presiden setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945 adalah sangat berkurang. Karena kewenangan dulunya yang termasuk merupakan hak prerogatif, namun untuk sekarang dalam pelaksanaannya ternyata memerlukan dukungan daripada lembaga negara lain, yaitu baik itu dalam bentuk persetujuan maupun pertimbangan politik dari DPR. Apakah dengan demikian, masih dapat kemudian untuk kita dikatakan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif? Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan konsepsi hak prerogatif menurut anggota MPR yang melakukan amandemen terhadap Pasal 14 UUD 1945? B. Amandemen Kedua Terjadi Pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 18 Agustus 2000. Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal
I Gusti Ngurah Santika, SPd
545
20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab Xll, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan Dalam Kaitannya Dengan Pemerintahan Daerah Menurut UUD 1945. Dengan semakin banyak pasal-pasal yang diamandemen dalam perubahan kedua UUD 1945, ternyata tidak membuat perubahan menjadi semakin baik. Kemudian dapat pula dilihat kembali berkaitan dengan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Ternyata dalam ketentuan tersebut terdapat kata dibagi atas yang pada dasarnya telah menunjukan ciri daripada bentuk negara kesatuan. Dikatakan demikian, memang dikarenakan pengaturan tersebut telah menunjukan hierarki yang cukup jelas antara Indonesia sebagai puncaknya daripada negara kesatuan. Kemudian diikuti pula oleh provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian daripada daerah, yang posisinya berada tepat di bawah kedaulatan negara Indonesia. Hal mana juga merupakan suatu usaha, sebagai koreksi terhadap karakteristik sistem pemerintahan daerah pada waktu itu. Yang mana ketika itu, sangat mengidealkan pola hubungan fungsional horizontal alias tidak hierarkis antara satu daerah dengan daerah lainnya, terutama dalam hal ini antara bagian provinsi dengan kabupaten, yang kenyataannya memang dianut oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dan ternyata benar saja, bahwa UU yang lahir di zaman reformasi tersebut, mendapatkan kritik yang begitu tajam dari kalangan luas, termasuk juga rakyat di samping para ahli. Untuk menghadapi kritikan yang luas dari elit pemerintahan dan masyarakat tersebut, maka pada amandemen kedua UUD 1945, ditegaskanlah kembali prinsip hierarki di Indonesia sebagai suatu negara dengan bentuk kesatuan, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Adanya ketentuan tersebut, tidak lain dikarenakan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah povinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota tidak bersifat hierarkis, namun bersifat fungsional horizontal, maka fungsi koordinasi yang dilakukan antara pemerintah satu dengan pemerintah di bawah lainnya sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, pada tahun 2000, MPR merumuskan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang di dalam kalimat tersebut terdapat kata dibagi atas, pembagian kekuasaan ini kemudian disebut dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, antara pemerintah pusat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
546
dan daerah, yang selanjutnya dapat disebut sebagai daerah otonom. Daerah otonom tersebut selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mardiasmo,2011;12). Namun, dalam sejarah perjalanannya ternyata banyak yang belum menyadari, bahwa adanya struktur hierarkis pemerintahan yang telah dianut oleh UUD 1945, mulai dari pemerintah pusat, kemudian di bawahnya lagi ada provinsi dan kabupaten/kota. Tetapi, dalam kenyataannya para pejabat negara, khususnya di daerah otonom seperti provinsi, kabupaten/kota, ternyata tidak bijak dalam menyikapi lahirnya ketentuan tersebut. Tidak lain dikarenakan merasa, bahwa mereka duduk sebagai pejabat yang telah ditentukan untuk kemudian dipilih oleh rakyat secara langsung. Sehingga dengan begitu, berarti juga secara otomatis memiliki legitimasi yang kuat, dan merasa tidak perlu untuk tunduk dan patuh kepada daerah lainnya, termasuk juga kepada pusat, dalam menjalankan kewenangannya, terutama kewenangan yang memang berikan oleh UU. Apapun tafsiran orang terhadap desentralisasi, yang memberi wewenang seluas-luasnya kepada bupati/walikota, tampaknya tidak dapat diterima kemungkinan (tipe pemerintahan ini) menimbulkan godaan lebih besar untuk kembali ke sentralisasi kekuasaan ketika pembangunan didefinisikan sebagai upaya yang mencakup redistribusi kekuasaan dan sumber daya, yang mengasumsikan bahwa hanya otoritas yang mempunyai landasan luas yang dapat melaksanakan perubahan yang dikehendaki dengan hasil baik (Atmaja,2002;7). Dengan demikian, perilaku yang seperti itu oleh pejabat pemerintahan daerah, akan menjadi faktor pendorong yang mungkin saja, bisa menyebabkan kembalinya Indonesia ke dalam bentuk sentralisasi kekuasaan oleh pusat, seperti yang terjadi pada masa lalu. Tidak lain dikarenakan, jika dilihat kemudian bahwa sebenarnya pusat memiliki kewenangan yang jauh lebih besar apabila dibandingkan daerah. Tentunya pendapat tersebut dikatakan, karena memang jika kita lihat kembali dari konsep bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, dengan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945). Pusat memiliki kewenangan untuk mengatur semua yang ada di dalam wilayahnya, merupakan ciri utama dari bentuk negara kesatuan. Jadi, untuk ke depannya daerah sebenarnya harus menyadari, bahwa kewenangan yang diberikan kepadanya lewat atribusi UUD 1945, terutama dalam bentuk undang-undang tidaklah bersifat mutlak. Sebab dapat saja, pusat sebagai penguasa yang benar-benar berwenang, kemudian melakukan perubahan terhadap undang-undang, yang sebenarnya menjadi dasar daripada daerah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan hak otonomi tersebut. Sebab kewenangan yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
547
dimiliki oleh daerah harus pula dilandasi oleh prinsip-prinsip negara kesatuan, bukan negara yang semata hanya berdasarkan atas kekuasaan (machsstaat). Walaupun sebenarnya undang-undang pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada daerah-daerah di Indonesia, untuk selanjutnya mengatur urusannya sendiri berdasarkan hak otonomi yang kemudian dimilikinya. Memang tuntutan reformasi, untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi daerah, berupa hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah, ternyata banyak menonjolkan segi negatifnya, walaupun dalam kenyataannya tidaklah menampik adanya sisi positif, yang telah dihasilkan. Pendapat tersebut dilontarkan, dikarenakan dengan kewenangan yang nyata dan begitu luas, dalam kenyataanya daerah merasa untuk tidak perlu bergantung dengan pemerintah pusat, yang sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang bentuk negara kesatuan, harusnya daerah tetap memperhatikan tingkat pemerintahan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya kesenjangan antara pemerintah di atasnya, dengan tingkatan pemerintahan yang berkedudukan di bawahnya. Inilah implikasi dari otonomi yang diberikan terlalu luas kepada daerah, sehingga secara tidak langsung menyebabkan timbulnya raja-raja kecil, seperti zaman sebelum kemerdekaan. Namun, jika dibandingkan dengan ketentuan ayat (5) dari Pasal 18 UUD 1945, maka kita tidak akan heran dengan adanya prilaku aneh dari para pemegang kekuasaan di daerah yang seperti itu, bahkan dalam perjalanannya, pemerintahan di bawah, ternyata secara terang-terangan berani untuk kemudian menentang pemerintahan yang ada di atasnya, termasuk pula terhadap pemerintah pusat. Tidak lain, karena dalam ketentuan ayat (5) dari Pasal 18 UUD 1945 ini, memang dapat kemudian kita temukan pengaturan yang mengandung ciri daripada bentuk negara federal. Dikarenakan seperti biasanya bahwa dalam negara federal, telah ditentukan tentang adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah serikat dan pemerintah negara bagian. Misalnya saja ditentukan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah serikat secara terperinci dan selain kekuasaan yang dimaksudkan tersebut, tentunya yang menjalankan kekuasaan sisanya adalah pemerintah negara bagian. Seperti misalnya ditentukan dengan tegas dalam ketentuan konstitusi, bahwa pemerintah serikat mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan angkatan bersenjata, hubungan luar negeri dan beberapa urusan lainnya yang ditentukan secara jelas. Kemudian selain tugas yang dijalankan oleh serikat tersebut, kemudian akan diserahkan kewenangannya kepada negara bagian. Sehingga nantinya akan terlihat dengan jelas, mana yang merupakan tugas serikat dan mana tugas daripada negara bagian. Hal mana pada dasarnya tidak boleh saling mencampuri urusan satu sama lainnya, sehingga tidak akan pernah ada tumpang tindih berkaitan dengan tugas masing-masing dalam negara serikat tersebut. Untuk lebih jelasnya, berkaitan dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
548
adanya pembagian kekuasaan serikat dengan negara bagian, maka patutlah dikutif pendapat Strong (2005;140) yang menyatakan bahwa. Kekuasaan bisa didistribusikan dengan salah satu dari dua cara berikut : konstitusi merumuskan kekuasaan yang dimiliki otoritas federal dan menyerahkan sisanya kepada unit-unit federasi, atau konstitusi merumuskan kekuasaan yang dimiliki unitunit federasi dan menyerahkan sisanya kepada otoritas federal. Sisa kekuasaan itu umumnya disebut dengan istilah reserve of power, kekuasaan simpanan. Kemudian sebaliknya, ada negara federal yang memang dalam kenyataannya memberikan kekuasaan simpanan/sisa (reserve of power) kepada negara-negara bagian, sedangkan berkaitan dengan kekuasaan yang dipegang oleh serikat telah ditentukan secara jelas, kekuasaan yang kemudian akan dijalankannya. Prinsip yang sama terkait dengan pembagian kekuasaan seperti tersebut di atas, dapat juga kita temui kembali dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yang pada prinsipnya mengatur semua urusan bersifat otonom atau desentralistis adalah milik daerah, yang hanya dikecualikan jika dalam undang-undang ditentukan bahwa urusan tersebut akan menjadi bagian daripada urusan pemerintahan pusat. Dengan demikian, undang-undanglah telah menentukan dengan tegas mana yang merupakan kekuasaan pusat, sedangkan berkaitan dengan tugas yang tidak dicantumkan secara tegas (reserve of power) selanjutnya akan menjadi urusan daerah. Tentunya prinsip pembagian kekuasaan seperti dinyatakan tersebut, hanya mungkin dapat ditemui kembali jika seandainya negara tersebut menganut bentuk negara federal. Di mana pada dasarnya prinsip pembagian kekuasaan tersebut, adalah bertujuan untuk memperkuat negara bagian, sehingga pemerintah serikat tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap negara bagian. Dengan kekuasaan sisa yang dimiliki oleh daerah, maka pusat hanya terbatas dalam melakukan tugas-tugasnya, yang sebelumnya telah ditentukan secara tegas dalam batas-batas undang-undang. Namun, ada juga negara yang berbentuk federal, ternyata terkait dengan prinsip pembagian kekuasaan merinci satu persatu kekuasaan yang dipegang oleh negara bagian secara pasti, yang kemudian diikuti sisa kekuasaan tidaklah disebutkan untuk kemudian menjadi kewenangan serikat. Adanya prinsip pembagian kekuasaan seperti tersebut di atas, adalah semata-mata bertujuan untuk membatasi kekuasaan daripada negara bagian. Dan mungkin saja selanjutnya, karena terlalu besarnya kekuasaan sisa yang dimiliki oleh serikat, secara tidak langsung akan menyebabkan tipisnya perbedaan antara bentuk negara serikat, dengan negara yang pada dasarnya berbentuk kesatuan. Sehingga pada kenyataannya negara federal tersebut kemudian lebih mendekati bentuk negara kesatuan. Jika dianalisis berdasarkan teori seperti tersebut di atas, maka dalam ketentuan ayat (5) dari Pasal 18 UUD 1945 tersebut, yang pada dasarnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
549
menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa ketentuan ayat (5) dari Pasal 18 UUD 1945, sangat mirip dengan ketentuan tentang prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dalam negara berbentuk federal. Karena ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga ditentukan prinsip pembagian kekuasaan yang sama, terutama dengan mengikuti pola-pola dalam negara yang memang berbentuk negara federal. Hanya saja, untuk lebih rincinya kekuasaan mana yang menjadi kekuasaan pusat dan daerah, masih harus kemudian ditentukan kembali dalam bentuk undang-undang. Jadi, dalam berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, ternyata lembaga legislatif pusat masih memiliki kewenangan untuk kemudian menditribusikan kembali kekuasaan kepada daerah, dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya, sebagaimana dimaksudkan kemudian dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Sehingga seberapa luasnya otonomi daerah nantinya, untuk itu akan ditentukan kembali dalam bentuk undang-undang sebagai pengaturannya. Sehingga semua yang terkait dengan masalah tersebut, masih sangat tergantung daripada kehendak badan legislatif pusat itu sendiri. Jika dipandang dari sudut ini, maka tentunya kemudian akan terlihat kembali mengandung ciri daripada bentuk negara kesatuan. Hal ini dikarenakan, bahwa kekuasaan yang diberikan oleh pusat kepada daerah ternyata ditentukan dalam undang-undang, sedangkan kalau kita lihat kembali bahwa undang-undang itu sendiri pada hakekatnya dibuat oleh organ legislatif pusat, bukan oleh organ legislatif yang ada di daerah. Tentunya pernyataan tersebut adalah sesuai dengan ciri daripada bentuk negara kesatuan, seperti adanya (1) supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat, (2) tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat (Budiardjo,2008;270, lihat juga C.F.Strong,2005;111 bandingkan dengan, K.C Wheare,2005;30). Bedanya prinisp pembagian kekuasaan antara negara yang bentuk serikat dengan negara kesatuan untuk kasus di Indonesia, bahwa biasanya dalam negara serikat prinsip pembagian kekuasaan antara pemerintah serikat dengan negara bagian berkaitan masalah-masalah yang kemudian menjadi urusan serta kompetensi masing-masing antara kedua pemerintahan negara tersebut, yaitu serikat dan negara bagian memang telah ditentukan dengan tegas dalam konstitusi serikat. Namun, khusus untuk di Indonesia prinsip pembagian kekuasaan, berkaitan dengan urusan yang menjadi kompetensi masing-masing antara pusat dan daerah, tidak ditentukan secara jelas dalam UUD 1945, mengenai apa saja yang merupakan kewenangan pusat maupun daerah, melainkan diserahkan kembali pengaturannya lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Dengan begitu, pusat khususnya lembaga legislatifnya memiliki kewenangan untuk selanjutnya mengatur secara rinci, apa yang kemudian menjadi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
550
urusan daripada pusat dan selanjutnya menyerahkan urusan sisanya kepada daerah untuk kemudian diselenggarakan. Dari paparan tersebut di atas, yang hanya mungkin dapat dilakukan untuk kemudian memperkecil jarak yang ada antara idealitas dengan realitas dalam undang-undang dasar, yaitu hanya dengan cara memegang kata kuncinya pada waktu pembentukan undangundang. Misalnya dikatakan bahwa pemerintahan pusat memegang kekuasaan terhadap masalah-masalah tertentu, seperti yang ditetapkan di dalamnya (undang-undang), kemudian selain kekuasaan yang ditetapkan tersebut dalam undang-undang berkaitan dengan urusanurusan yang memang dikuasai oleh pusat dinyatakan adalah milik daerah. Maka tentunya untuk sekarang ini, pusat perlu menetapkan kekuasaan sebanyak-banyaknya di dalam undang-undang, agar daerah tidak terlalu banyak memiliki kekuasaan sebagai sisa kekuasaan dari pusat. Sehingga ciri yang terkandung seperti dalam konsep negara federal dapatlah sedikit dikurangi. Dengan demikian, perlu ditentukan tidak hanya kewenangan dalam bidang, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal dan moneter, dan agama (Pasal 10 Ayat (3) UU No 32 Tahun 2004) yang kemudian menjadi kewenangan pusat. Tetapi seharusnya juga meliputi urusan-urusan yang memang belum dapat untuk ditangani oleh daerah secara efektif. Tidak hanya itu saja, yang seharusnya ditangani oleh pusat melainkan juga menyangkut berbagai kepentingan nasional, yang menguasai hajat hidup orang banyak, tentunya tidak mungkin dapat diberikan pengelolaannya kepada daerah. Namun, jika cermati secara saksama lagi seperti dalam ketentuan ayat (6) dari Pasal 18 UUD 1945, dinyatakan bahwa daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan hak otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi pemerintahan dan dekonsentrasi kekuasaan. Pengertian otonomi di sini adalah daerah memiliki kewenangan melakukan pengelolaan wilayah baik melalui penerbitan kebijakan daerah (peraturan daerah, sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang (Ranadireksa,2009;189). Di dalam ketentuan Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah/Otonomi Daerah telah diatur berkaitan dengan kewenangan untuk membetuk peraturan daerah. Selanjutnya kita mungkin dapat lebih mengetahui bahwa setelah berlakunya peraturan daerah, ternyata paling lambat tujuh hari (setelah ditetapkan,) maka peraturan daerah tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat sebagaimana dimaksudkan tersebut dalam kenyataannya diwakili Menteri Dalam Negeri. Dan jika suatu peraturan daerah yang berlaku, ternyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum (ayat (2) Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004), maka dapat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
551
dibatalkan, yang berarti ketidakabsahannya berlaku sejak tanggal adanya pembatalan. Bukannya batal demi hukum yang berarti ketidakabsahannya berlaku sejak peraturan itu ditetapkan (yang berarti pula membatalkan pula akibat-akibat hukum yang timbul sebelum ada pembatalan). Ini merupakan salah satu mekanisme kontrol yang dilakukan oleh pusat terhadap daerah, sebagai suatu wujud daripada prinsip bentuk negara kesatuan. Dan tentu dengan adanya ketentuan ini, dapat kemudian dikatakan telah mengandung ciri daripada bentuk negara kesatuan, terutama sebagai bentuk pembatasan terhadap luasnya otonomi yang telah diberikan oleh pusat kepada daerah. Namun, penulis kemudian berpendapat bahwa berkaitan dengan hal tersebut adalah sungguh berlebihan, jika ternyata dalam UUD 1945 telah dicantumkan mengenai kewenangan daerah untuk menetapkan peraturan daerah. Karena lazimnya peraturan daerah tidak perlu untuk dicantumkan dalam UUD 1945, karena pada prinsipnya Indonesia adalah negara kesatuan, yang pastinya akan berbeda jika negara tersebut menganut bentuk federal. Cukuplah kalau pemberian kewenangan untuk membuat peraturan daerah, tidak perlu diberikan langsung oleh UUD 1945, melainkan seharusnya merupakan kewenangan daripada lembaga legislatif pusat, yang selanjutnya memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka membentuk peraturan daerah. Sehingga, masalah-masalah apa saja yang selanjutnya perlu untuk diatur kembali oleh daerah, berkaitan dengan hak otonomi yang diberikan kepada daerah tersebut tentunya sangat tergantung kepada badan legislatif pusat. Penulis beranggapan bahwa perumusan kewenangan atribusi dalam pembentukan Peraturan Daerah secara langsung dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 perubahan, adalah terlalu berlebihan (Indrati,2007;181). Dengan demikian, badan legislatif pusat yang sebenarnya merupakan lembaga utama dalam negara kesatuan, seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk membuat pengaturan tentang pemberian kewenangan kepada daerah untuk membentuk perda. Sehingga kemudian dapat menentukan apakah selanjutnya akan memberikan kewenangan kepada daerah, untuk dapat membentuk peraturan daerah, yang mana semua ini merupakan suatu prinsip atau ciri untuk mengenali apakah negara tersebut berbentuk kesatuan. Dengan demikian, terdapat dua sifat yang penting dari bentuk negara kesatuan, yaitu: adanya supremasi parlemen pusat, dan tidak adanya badan berdaulat tambahan lainnya. Dengan demikian, pusat seharusnya memiliki kekuasaan dalam rangka mengatur semua urusan pemerintahan termasuk juga daerah bagian, yang dalam hal ini adalah provinsi dan kabupaten/kota. Jadi dapatlah kemudian dikatakan bahwa kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah, adalah dalam rangka untuk mengatur lebih lanjut kewenangan yang memang diberikan oleh pusat kepada daerah, terutama dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dan ini pun sebenarnya tidak dapat dilakukan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
552
seenaknya oleh daerah, terutama pada saat membentuk peraturan daerah untuk mengatur kembali kewenangan yang diberikan oleh pusat kepadanya. Karena jika dalam kenyataannya peraturan daerah yang dibentuk tersebut, ternyata kelak benar-benar bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi ataupun kepentingan umum, maka dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, sebagai bentuk kontrol daripada pusat terhadap daerah. Sehingga dengan adanya kontrol dari pemerintah pusat terhadap daerah, merupakan suatu konsekuensi daripada bentuk negara kesatuan yang memang dianut oleh Indonesia. Jadi, adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri itu tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab dalam kenyataannya pengawasan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat (Budiardjo,2008;270). Namun, terkait dengan adanya ketentuan pengujian peraturan daerah oleh pemerintah pusat, penulis sangat keberatan terhadap ketentuan 145 UU No. 32 Tahun 2004 tersebut. Menurut penulis kelemahannya yang mungkin dapat ditemukan dalam pengujian peraturan daerah, yaitu pada lembaga yang mempunyai kewenangan atau badan (organ) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, untuk kemudian membatalkan suatu peraturan daerah yang diduga telah bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi atau kepentingan umum. Lembaga yang dimaksud oleh undangundang tersebut adalah pemerintah pusat, yang dalam realitasnya diwakili oleh Menteri Dalam Negeri. Yang kemudian menjadi pertanyaan mendasar, yaitu mengapa yang berhak untuk melakukan pengujian (review) terhadap peraturan daerah diberikan kepada pemerintah pusat (eksekutif), yang menurut penulis merupakan salah satu lembaga politik yang berada di pusat? Sedangkan penulis berpendapat bahwa mengenai peraturan daerah yang telah diuji itu, sebenarnya merupakan produk wakil rakyat, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, yang merupakan satu kesatuan sebagai pemerintahan daerah. Penulis mengatakan kedua lembaga daerah tersebut sebagai wakil rakyat, tentu dikarenakan bahwa kedua organ daerah tersebut yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah, merupakan lembaga yang pengisian jabatannya maupun keanggotaannya, memang melibatkan rakyat secara langsung, lewat pemberian suara pada saat pemilihan umum (baik pileg maupun pilkada). Selain itu juga, perlu kemudian untuk diketahui bahwa peraturan daerah yang diuji oleh pemerintah pusat tersebut, adalah peraturan daerah sudah mengikat secara hukum, karena memang sudah ditempatkan (diundangkan) pada lembaran daerah. Hal mana tentu akan berbeda maknanya, jika saja pengujian yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut, dilakukan sebelum ditetapkannya peraturan daerah tersebut mengikat secara hukum atau sudah ditempatkan dalam lembaran daerah. Atau dapatlah dikatakan, jika
I Gusti Ngurah Santika, SPd
553
setelah ditetapkan perda selanjutnya adanya batas tenggang waktu bagi berlakunya rancangan peraturan daerah tersebut, sampai kemudian adanya uji materiil terhadap rancangan perda tersebut, barulah berlaku kemudian, setelah adanya pengujian rancangan peraturan daerah yang memang belum diundangkan dalam lembaran negara. Jika dalam kenyataannya tidak bertentangan. maka barulah kemudian diundangkan dalam lembaran daerah, maka dengan demikian penulis rasa tidak akan ada masalah dikemudian hari, berkaitan dengan legitimasi pengujian perda tersebut. Artinya, jika sebelum diundangkan perda tersebut, maka terkait dengan kekuatan berlakunya perda tersebut belumlah dapat dilaksanakan, hal mana dikarenakan belum dapat mengikat secara umum. Tidak lain dikarenakan, bahwa mengikatnya suatu peraturan daerah perlu untuk selanjutnya diundangkan dalam lembaran daerah. Dalam hal ini, apakah konsep pengujian peraturan daerah tersebut, tidak bertentangan dengan supremasi hukum yang sebenarnya kita anut, seperti apa yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Karena pada dasarnya sebuah perda, yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat (DPRD) bersama dengan kepala daerah, setelah mendapatkan persetujuan bersama adalah bersifat mengikat. Dikarenakan kemudian setelah rancangan perda tersebut diundangkan dalam lembaran daerah dan menjadi hukum, namun dalam kenyataannya dibatalkan oleh lembaga politik yang ada di pusat, dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, masih harus dicari lagi dasar legitimasi daripada ketentuan Pasal 145 UU No 32 Tahun 2004, berkaitan dengan adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk kemudian membatalkan peraturan daerah, yang sudah diundangkan dalam lembaran daerah, hal mana tentunya peraturan daerah tersebut, sudah memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Tentunya sebagai hukum yang bersifat mengikat, seharusnya terkait dengan segala penafsirannya tidak lagi berdasarkan kehendak politik, walaupun kewenangan untuk pembatalan peraturan daerah tersebut diserahkan kepada pusat melalui undang-undang. Namun, tetap saja filosofinya bahwa hukum yang kemudian ditafsirkan oleh lembaga politik adalah merupakan penafsiran yang pada dasarnya bersifat politis. Apakah perda itu kemudian bertentangan dengan hukum yang kedudukannya lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum, penafsiran tersebut selanjutnya akan selalu tergantung pula pada faktor-faktor politis. Karena faktor politislah yang lebih mendominasi penafsiran peraturan daerah, apakah sesuai atau tidak dengan syarat-syarat yang telah dicantumkan dalam ketentuan Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004, untuk selanjutnya dibatalkan atau tidak oleh pemerintah pusat. Tentunya berkaitan dengan pengujian peraturan daerah yang tersirat lebih menonjol adalah hukum harus mengalah pada tafsiran politik, yang berarti kedudukan hukum berada tepat di
I Gusti Ngurah Santika, SPd
554
bawah politik, namun sudah seharusnya politiklah yang kemudian tunduk kepada hukum. Apalagi dalam tataran ide atau cita hukum, lebih-lebih di negara yang menganut supremasi hukum, politiklah yang harus diposisikan sebagai variabel yang terpengaruh (dependent variable) oleh hukum (Mahmud MD,2011;4). Argumen penulis di atas bukanlah tanpa alasan, karena dapat saja dicontohkan dalam suatu daerah yang mayoritas pemenangnya adalah partai politik A, sedangkan partai politik yang menang di pusat atau sedang berkuasa adalah partai politik B. Ternyata partai politik B di daerah tersebut, bukanlah partai politik yang menjadi mayoritas dalam arti sebagai pemenang, dengan kata lain partai politik B tidak akan mampu mengalahkan partai politik A yang memiliki suara mayoritas di DPRD, dalam pengambilan keputusan di daerah tersebut. Maka untuk selanjutnya yang menjadi masalah, adalah legitimasi dari kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah yang sebenarnya sudah berkuatan hukum tetap, namun hanya dengan suatu keputusan politik. Hal mana tidak lain karena dasar daripada susunan pemerintahan pusat, termasuk dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, yang dalam kenyataannya merupakan orang dari partai politik. Bisa saja, karena partai politik B dengan alasan tertentu, hal mana karena merasa dirugikan dengan keputusan yang dihasilkan tersebut, walaupun sebenarnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum, maka dapat saja kemudian menyatakan batal terhadap suatu perda tertentu. Bahkan dengan masih adanya kata kepentingan umum yang pada dasarnya merupakan kata bersifat fleksibel, sehingga sungguh sangat mudah untuk kemudian ditafsirkan oleh penguasa. Jadi untuk itu, perlu ada kriteria yang dapat memberikan kejelasan tentang apakah sebenarnya dimaksudkan dengan kepentingan umum. Karena setiap ada kata kepentingan umum maka dalam kenyataannya kewenangan untuk penafsirannya selalu saja menggunakan penafsiran sepihak dari pusat. Sehingga seolah-olah pusat kemudian menjadi penafsir utama, berkaitan dengan apa yang selanjutnya disebut kepentingan umum, yang dalam kenyataannya penafsiran tersebut, hanyalah merupakan kepentingan dari pemerintah pusat saja. Belum jelasnya pengertian konsep daripada kepentingan umum itulah, yang tentunya mungkin dapat menjadi senjata utama bagi pemerintah pusat kemudian, untuk dapat membatalkan peraturan daerah tersebut. Sehingga terlihat tidak jelaslah mana yang sebenarnya merupakan konsep kepentingan umum dengan konsep pengertian kepentingan politik. Karena seolah-olah kedua masalah tersebut tidak ada bedanya, tidak lain dikarenakan penafsiran keduanya tersebut berada pada satu badan yang berkuasa, yaitu pemerintah pusat. Oleh karena itu, penulis mempunyai solusi dalam pengujian peraturan daerah, yaitu sebaiknya agar peraturan daerah jika benar-benar dianggap bertentangan dengan peraturan yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
555
kedudukannya lebih tinggi ataupun bertentangan dengan kepentingan umum, untuk kemudian diajukan saja ke MA agar selanjutnya diuji (yudicial riview). Dikarenakan MA adalah suatu lembaga hukum, yang tentunya pertimbangan-pertimbanganya merupakan suatu pertimbangan dengan dasar hukum yang jelas, bukan hanya pertimbangan politik saja seperti yang kemudian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan, bahwa setelah adanya keberatan atas Perpres tentang pembatalan perda tersebut, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Kepala Daerah atas inisiatifnya dapat pula mengajukan keberatan ke MA terhadap Perpres tersebut (Pasal 145 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004). Berarti adanya pembatalan terhadap peraturan daerah oleh pemerintah pusat yang dalam realitasnya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan menggunakan bentuk Peraturan Presiden. Artinya mekanisme terhadap pengujian atas Perpres tersebut ke MA, merupakan tindakan MA untuk menguji, apakah Peraturan Presiden yang ditetapkan untuk membatalkan perda tersebut, sebenarnya bertentangan atau tidak dengan undang-undang yang ada di atasnya. Dalam pengujian perda itu, apakah memang tepat keluarnya Peraturan Presiden tersebut, yang kemudian dalam kenyataannya secara tegas membatalkan peraturan daerah, dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi ataupun kepentingan umum. Ditentukan juga apabila setelah adanya Peraturan Presiden yang membatalkan peraturan daerah, maka kepala daerahlah kemudian yang jika merasa berkeberatan terhadap adanya Peraturan Presiden yang membatalkan perda tersebut. Untuk itu, kepala daerah dapat mengajukan keberatan tersebut kepada MA untuk diuji (yudicial review) atas Perpres pembatalan perda, apakah dapat dibenarkan terkait dengan kesesuaian keluarnya Peraturan Presiden dengan alasan yang memang terdapat didalam undang-undang, sehingga pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa terkait dengan kewenangan untuk melakukan yudicial review oleh MA terhadap pembatalan peraturan daerah dengan Perpres, yang jika tidak disetujui hanya dapat diajukan kemudian oleh kepala daerah. Berarti legal standing dalam pengujian Perpres terhadap pembatan perda hanyalah berada kepala daerah, dikarenakan merasa dirugikan hak-haknya atas terjadinya pembatalan peraturan daerah tersebut. Hal ini tidak lain dikarenakan, kepala daerah sendiri merupakan salah satu organ yang bertugas untuk membentuk peraturan daerah. Jadi perlulah kiranya kemudian, kepala daerah sangat berkeberatan terhadap adanya pembatalan perda oleh pemerintah pusat. Namun, jika hal itu yang kemudian dijadikan argumentasi, tentunya tidak mungkin bisa hanya memberikan kewenangan kepada kepala daerah saja, berupa kedudukan hukum untuk selanjutnya mengajukan keberatan terhadap adanya keputusan pembatalan oleh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
556
pemerintah pusat terhadap peraturan daerah. Bagaimana dengan DPRD, yang juga merupakan bagian daripada pemerintahan daerah (lihat Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004), sehingga ia juga merupakan lembaga yang berwenang untuk ikut pula atau terlibat langsung dalam membentuk peraturan daerah tersebut bersama-sama dengan kepala daerah sampai akhirnya mendapatkan persetujuan bersama? (lihat Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004). Untuk itu, menurut penulis kedudukan hukum berkaitan dengan adanya hak untuk mengajukan perpres tersebut ke MA, seharusnya tidak hanya diberikan kepada kepala daerah. Namun, untuk itu harus pula ikut melibatkan DPRD sebagai sebuah institusi, harusnya dipandang memiliki kepentingan langsung terhadap peraturan daerah yang memang dibentuknya, namun ternyata dibatalkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, DPRD dan kepala daerah yang merupakan bagian daripada pemerintahan daerah, secara hukum merupakan organ daerah yang kedudukannya sebagai satu kesatuan, tentunya memiliki kedudukan yang sama untuk kemudian mengajukan yudicial riview terhadap Perpres yang membatalkan perda tersebut kepada MA. Selain alasan sebagaimana dimaksudkan terutama dari sisi hukum di atas, maka jika kita selanjutnya tinjau sekali lagi, terutama dari sudut politiknya, maka pendapat penulis tersebut di atas, tentunya akan menjadi lebih kuat lagi. Kita tahu bahwa gubernur/bupati/walikota sebagai kepala daerah dapat dicalonkan oleh partai politik, di samping untuk sekarang dapat juga melalui perseorangan (lihat UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Penulis andaikan bahwa, kepala daerah yang dicalonkan partai politik pada saat pemilihan umum, ternyata memiliki pendukung minoritas di DPRD, sedangkan dilain pihak kemudian gubernur ternyata tidak dapat pula memanfaatkan kekuatan partai politiknya di DPRD, untuk membentuk peraturan daerah yang sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dengan adanya ketentuan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap peraturan daerah, terutama dalam bentuk pembatalan perda. Maka dapat saja kemudian kepala daerah yang sebenarnya merupakan bagian dari partai politik minoritas di daerah, namun bisa saja merupakan bagian dari partai politik mayoritas yang berada di pusat, kemudian tentunya dapat saja memanfaatkan peraturan ini. Bisa saja dikemudian hari ternyata peraturan daerah tersebut, dibatalkan oleh pemerintah pusat dengan Peraturan Presiden sebagai bentuknya. Tentunya dengan kedudukan hukum yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai satu-satunya pihak pemohon, untuk kemudian mengajukan ke MA terkait dengan Perpres tentang pembatalan peraturan daerah tersebut, akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tentu dikarenakan kepala daerah yang memiliki hak sebagai pemohon, untuk membatalkan Perpres tersebut melalui pengujian ke MA tidak mungkin akan digunakan. Hal ini tidak lain dikarenakan, memang dari semula kepala
I Gusti Ngurah Santika, SPd
557
daerah sangat menghendaki agar kemudian peraturan daerah tersebut dibatalkan oleh pemerintah pusat. Bahkan bisa saja kepala daerah tersebut, juga merupakan dari partai politik yang sama dengan pemerintah pusat, tetapi berbeda dengan partai politik yang ada di daerah, bahkan merupakan partai politik yang memiliki suara minoritas di DPRD. Itulah alasan yang menjadi dasar kenapa kedudukan hukum, terkait dengan keberatan atas Perpres pembatalan peraturan daerah yang diajukan ke MA untuk diuji, tidak hanya dimiliki oleh kepala daerah, namun perlu juga untuk ikut melibatkan DPRD sebagai unsur dalam pemerintahan daerah. Bahkan perlulah legal standing berkaitan dengan permohonan pengujian terhadap Peraturan Presiden tersebut kepada MA, diberikan pula kepada semua warga masyarakat di daerah tempat perda yang berlaku tersebut dibatalkan. Tidak lain dikarenakan perda tersebut merupakan bentuk peraturan yang sudah memiliki kekuatan hukum untuk mengikat masyarakat daerah tersebut, jadi sudah mengikat umum. Jadi, tentunya bisa saja, bukan hanya kepala daerah dan DPRD yang merasa dirugikan, oleh adanya pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Perpres terhadap perda tersebut, melainkan juga masyarakat luas terutama yang ada di daerah tersebut. Dikarenakan dapat saja masyarakat tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap perda yang dibatalkan tersebut. Kemudian kita kembali kepada kewenangan dalam bentuk pengujian peraturan daerah oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu merupakan suatu proses yang dapat dipandang tidaklah demokratis, apalagi dalam negara yang meletakan kedudukan hukum sebagai tertinggi (superior). Bahkan terkait dengan lembaga yang berwenang untuk berperan secara aktif dalam pengujian perda, menurut Wibawa dalam (Dwiyanto,2005;76) meskipun dengan pendapat yang keliru menyatakan bahwa ketika suatu gubernur atau Presiden secara sepihak atau semena-mena membatalkan suatu perda kabupaten atau propinsi, keputusan ini belum berlaku jika belum dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun apa yang telah dinyatakan oleh Wibawa tersebut maksudnya adalah baik, tetapi terkait dengan adanya Perpres terhadap pembatalan perda ternyata bukanlah objek daripada yudicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dikarenakan telah ditentukan bahwa undang-undang lah yang menjadi objek yudicial review or constitutional review daripada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, untuk di bawahnya, yaitu pertentangan yang terjadi antara peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, ternyata Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan yudicial review, hal mana adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada masing-masing lembaga negara tersebut (bandingkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur kewenangan MA dan MK dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
558
menguji peraturan perundang-undangan). Terkait kembali dengan kewenangan pemerintah untuk menguji peraturan daerah dengan bentuk Peraturan Presiden (excutive review), jelas pula terlihat dalam ketentuan Pasal 24A UUD 1945, yang menyatakan bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam mekanisme pengujian peraturan tersebut penulis memiliki pendapat, bahwa peraturan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, ternyata tidaklah kemudian dapat golongkan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal tersebut dikarenakan, yang diuji MA hanyalah produk hukum dari Presiden, yang telah membatalkan peraturan daerah tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden, bukannya peraturan daerah yang kemudian diuji oleh MA dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Padahal jelas dinyatakan dalam ketentuan tersebut (24A ayat (1) UUD 1945) di mana sebenarnya perda adalah termasuk dalam pengertian perundangundangan sebagaimana dimaksudkan oleh UUD 1945, artinya bukan hanya Peraturan Presidenm tetapi bisa saja mencakup ketentuan yang berada di bawahnya. Dan berkaitan dengan pengujian peraturan daerah ternyata jelas sekali dikemukakan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian juga dapat lihat kembali dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011. Selain itu jika kita konsisten dengan undang-undang tersebut dan juga dengan maksud dari kata peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 di atas, dapatlah juga kemudian diartikan bahwa termasuk peraturan desa (sebagaimana dimaksudkan sebelumnya dalam UU No. 10 Tahun 2004). Terkait dengan peraturan daerah yang seharusnya juga merupakan objek dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Tidak lain karena memang jelas-jelas dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, seharusnya yang kemudian menjadi objek uji materi (yudicial review) oleh MA adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tetapi, terkait dengan pengujian peraturan desa oleh MA adalah tidak mungkin dilaksanakan, dan tentunya akan berbeda dengan maksud daripada UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 24A ayat (1), UUD 1945 terkait dengan pengertian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga untuk itu kita tidak harus mengikuti alur pikir dalam UU No. 10 Tahun 2004, tentunya karena hanya akan merepotkan MA jika harus menguji peraturan desa padahal begitu banyak desa di Indonesia. Sehingga UU No. 12 Tahun 2011 telah merubah pola pikir sebelumnya, yaitu
I Gusti Ngurah Santika, SPd
559
dengan tidak mencantumkan kembali peraturan desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kembali kepada permasalahan dalam UU No. 32 Tahun 2004, terkait dengan tidak dimaksudkannya peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah undang-undang. Tentunya hal tersebut adalah tidak sejalan dengan maksud daripada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan juga UU No. 10 Tahun 2004 serta dalam UU No.12 Tahun 2011. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang mana saja selanjutnya termasuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan yang mana tidak termasuk. Di karenakan dalam UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, telah menyatakan bahwa peraturan daerah adalah merupakan salah satu bentuk peraturan perundangundangan yang kedudukannya tepat berada di bawah undang-undang. Hal ini terbukti dengan diberikan kesempatan kepada masyarakat (perorangan warga negara Indonesia) untuk mengajukan peraturan daerah kepada MA, dengan alasan bahwa peraturan daerah tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yang dapat dilakukan baik melalui kasasi maupun secara langsung. Namun, penulis memiliki solusi, dikarenakan pada saat dibentuknya dan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 yang lebih dulu, jika dibandingkan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka pertentangan yang terjadi antara undang-undang tersebut di atas, dapatlah kemudian diatasi dengan menggunakan asas-asas hukum. Seperti jika UU No. 32 Tahun 2004 berhadapan dengan UU No.12 Tahun 2011, maka dapat diterapkan lex specialis derogate lex generali, ketentuan ini dapat digunakan untuk hal tersebut karena jika suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah sama, sedangkan dalam kenyataannya bertentangan antara satu undang-undang dengan udang-undang lainnya bertentangan, maka yang akan digunakan adalah ketentuan yang mengatur lebih khusus, berkaitan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hal yang sama. Yang diatur sama dalam UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011 adalah berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, maka yang berlaku kemudian dalam hal ini adalah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, selain itu ada asas hukum lain lagi, yang dapat melumpuhkan ketentuan yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2004, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, menurut penulis dapat saja kemudian dilawankan dengan undang-undang lainnya dalam bidang kekuasaan kehakiman, seperti UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2009 dll.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
560
Dengan demikian, yang berlaku terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut adalah undang-undang baru yang mengaturnya kemudian. Tentunya pernyataan tersebut adalah sesuai dengan asas hukum lex posteriori derogate legi priori, yang berarti jika ada undang-undang lama, yang kemudian ternyata mengatur juga ketentuan hal yang sama berkaitan dengan materi antara satu undang-undang, dengan ketentuan undangundang yang lain terutama dengan undang-undang baru, yang pada dasarnya bertentangan, maka undang-undang baru tersebutlah yang kemudian didahulukan keberlakuannya. Selain itu, permasalahan terkait dengan pemerintahan daerah, dapat ditemukan kembali dalam ketentuan ayat (4) Pasal 18 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota adalah dipilih secara demokratis. Kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah maksud kata dipilih secara demokratis itu, dapat disamakan maknanya dengan kata dipilih secara langsung?. Apakah kepala daerah yang dipilih oleh DPRD tidak sama demokratisnya, dengan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Menurut penulis, kata demokratis itu sebenarnya menunjuk pada suatu proses, mulai dari pencalonannya sebagai kepala daerah sampai dengan terpilihnya menjadi kepala daerah, haruslah melalui cara-cara demokratis. Dengan demikian, tentunya tidak melanggar norma hukum yang berlaku, di samping tidak melanggar norma-norma lainnya, baik norma moral, kesusilaan, dan yang lainnya dalam proses pemilihan kepala daerah. Sehingga dapatlah kemudian dikatakan, bahwa kepala daerah yang dipilih baik oleh DPRD, maupun oleh rakyat secara langsung adalah sebenarnya sama-sama demokratis. Asalkan pilihan dari keduanya tersebut adalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang memang dianut di dalam negara demokrasi sebagaimana mestinya. Karena terkait dengan hal tersebut hanyalah menyangkut masalah pilihan yang kemudian nantinya akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang, yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama Presiden, karena sudah ditentukan bahwa kedua lembaga negara itulah yang berwenang untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tetapi melihat situasi dan kondisi untuk sekarang ini, penulis kemudian beranggapan bahwa akan lebih baik, apabila nantinya pemilihan kepala daerah dikembalikan saja kepada DPRD. Hal tersebut dapat saja dilakukan, namun dengan catatan harus ada tranparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pemilihan terhadap kepala daerah, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi kolusi antara DPRD dan calon kepala daerah. Tidak lain dikarenakan selama ini, rakyat terlalu disibukan oleh berbagai macam pemilihan umum yang berlangsung bertubi-tubi, sehingga menyebabkan masyarakat mengalami kejenuhan politik. Dalam pada itu, tentunya akan berakibat terjadinya frustasi terhadap sistem poltik yang dianut, sehingga pada gilirannya mengurangi nilai dari kualitas demokrasi itu sendiri, yang sebenarnya hendak diwujudkan.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
561
Ditambah lagi, jika kemudian ditinjau dari sudut anggaran yang dikeluarkan dalam pesta demokrasi, untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lah dapat dikatakan sedikit. Dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pesta rakyat dalam perhelatan pemilu daerah, tentunya dapat pula dibandingkan dengan seberapa besar pencapaian, yang selama ini telah diraih oleh calon kepala daerah setelah nantinya dia terpilih menjadi kepala daerah. Tampaknya hasil yang dicapai selama ini, belumlah setara dengan anggaran/biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam mendukung pesta rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Sehingga, terlihat masih jauh dari apa yang sebenarnya menjadi harapan, dengan kenyataan yang terjadi setelah ia kemudian menjabat menjadi kepala daerah. Tanpa hasil memadai merupakan suatu ciri utama sebagaimana tampak sekali terlihat kemudian. Kegagalan dalam menjalankan amanat rakyat, setelah diadakan pemilihan umum untuk kepala daerah, terutama terkait dengan keberhasilan yang belum dapat dicapai, oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebelumnya. Besarnya biaya yang dikeluarkan dari APBD, juga diikuti kemungkinan akan ketidakmampuan seorang kepala daerah, yang pada dasarnya kepala daerah sendiri, merupakan hasil daripada pilihan rakyat untuk kemudian menjalankan tugasnya. Tentunya, menyebabkan kemiskinan kian hari kian bertambah banyak, bahkan menjadi pemandangan yang mencolok mata, dikarenakan banyaknya menyedot dana APBD, yang seharusnya dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyejahterakan rakyat. Namun, kemudian ternyata dihamburkan-hamburkan hanya untuk membiayai pesta demokrasi tersebut, yang belum tentu mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan amanat rakyat setelah nantinya calon kepala daerah tersebut menjabat. Di samping itu, ternyata dengan besarnya biaya yang telah dikeluarkan, bahkan tidak hanya biaya tersebut dikeluarkan oleh negara yang tentunya juga termasuk daerah melalui APBD. Namun, dalam realitasnya ternyata tidak kalah saing pula, dengan besarnya uang yang kemudian harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah, telah menyebabkan demokrasi mengarah ke plutokrasi, yang berarti hanya golongan berduit saja, selanjutnya dapat menjadi calon kepala daerah. Bahkan banyak pendapat mengatakan, bahwa hanya orangorang berduit saja lah, yang kemudian dengan mudah dapat menjadi calon kepala daerah. Kenyataannya akan lebih sulit jika orang benar-benar tidak mempunyai uang, apalagi untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi pencalonan sebagai kepala daerah dari partai politik tertentu, tidaklah dengan mudah dapat diraih. Sehingga dengan biaya sangat besar dikeluarkan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka untuk selanjutnya setelah menjabat, yang kemudian menjadi prioritas utama, bahkan mau tidak mau harus dilakukannya adalah bukan hanya untuk menyejahterakan rakyat. Karena perhitungan yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
562
paling penting untuk dilakukan, yaitu bagaimana caranya mengembalikan modal tersebut, agar biaya yang sebelumnya dikeluarkan, terutama pada saat pencalonannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti pada saat kampanye, dapatlah kembali sehingga tidak merugi. Setelah itu, barulah kemudian kepala daerah tersebut, selanjutnya mencari sedikit keuntungan, bahkan ada yang disertai dengan mengeruk keuangan negara, untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat di bawahnya yang telah memilihnya. Dengan besarnya wewenang, yang dimiliki setelah terpilih menjadi kepala daerah, tentunya membuat banyak kepala daerah tergiur untuk melakukan kegiatankegiatan, yang pada dasarnya kegiatan tersebut sifatnya sangat bertentangan dengan hukum. Hal mana terbukti dengan banyaknya kepala daerah, termasuk yang masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat lagi (baik karena tidak terpilih kembali maupun karena sudah menjabat dua kali) yang tersandung kasus korupsi. Sebenarnya dengan adanya pilkada ini, telah membuka berbagai peluang untuk melakukan tindakantindakan, yang dapat dipandang sesungguhnya sangat sifatnya bertentangan dengan hukum. Hal ini dapatlah dilihat kemudian dari disaat mulainya kampanye pemilu sampai dengan menjabat di saat menang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi jelas terlihat praktek-praktek yang pada hakekatnya adalah benar-benar tidak sesuai dengan prinsipprinsip negara demokrasi, terutama ditambah lagi dengan negara yang menganut paham negara hukum demokratis. Bahkan, banyak selanjutnya mengatakan bahwa dengan merebaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, penyebabnya tidak lain dikarenakan oleh besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah, khususnya pada saat pencalonannya sampai kemudian terpilih untuk menjabat sebagai kepala daerah. Dikarenakan, biaya besar yang sudah dikeluarkan pada saat menjadi calon kepala daerah, ternyata akan menjadi aneh dengan penghasilannya kemudian, pada saat menjabat menjadi kepala daerah tentunya sangat jauh timpang. Sehingga banyak orang mengatakan, bahwa yang menjadi salah satu penyebab dari mewabahnya korupsi di daerah yang dilakukan oleh kepala daerah, dikarenakan besarnya biaya yang sudah dikeluarkan oleh peserta, pada saat menjadi calon kepala daera. Dengan demikian, di manakah letak rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang sebelumnya telah ikut pula untuk terlibat secara langsung dengan memilih kepala daerah? Sejauh ini terlihat bahwa hasil kinerja daripada kepala daerah yang merupakan hasil pilihan rakyat, ternyata masih jauh dari harapan, untuk kemudian dapat mewujudkan semua janjinya tersebut, yaitu menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, sudah seharusnya para penyelenggara pemilu untuk kemudian memberi suatu pencerahan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menentukan pilihannya pada pemilu, misalnya, untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil WaliKota,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
563
setidaknya pada tingkat kriteria (Danim,2010;150). Dengan demikian, ke depannya diharapkan pilihan rakyat akan benar-benar mampu menyejahterakan mereka. Kenyataannya adalah setelah calon kepala daerah terpilih, ternyata banyak yang belum mampu, untuk kemudian mengemban amanat rakyat tersebut. Malahan, bukannya kesejahteraan rakyat yang memang diutamakan dengan adanya pemilu kepala daerah, namun malah pemilu tersebut menambah konflik di masyarakat. Tidak lain dikarenakan, pada saat kegiatan pemilu dalam kenyataannya terjadi peristiwa saling menghujat, dan saling melecehkan antara calon kepala daerah, yang jika kemudian kita saksikan kembali ternyata seringkali dapat menjadi pemicu masa di bawahnya. Bahkan dengan terjadi peristiwa seperti di atas, maka secara tidak langsung masa tersebut ternyata masuk ke dalam pusaran konflik politik. Sehingga yang kemudian terjadi, adalah bentrokanbentrokan fisik antara masa pendukung antara satu calon dengan masa pendukung calon kepala yang lainnya. Tentunya kemudian, kita dapat menganalisis kembali bahwa ketegangan yang telah terjadi di atas, terutama antara elit politik nantinya akan berimplikasi atau merambat terhadap masa pendukung, yang posisinya ada di bawah. Oleh karena itu, konflik antara elit politik kemudian akan menyebabkan merembes ke akar rumput, yaitu masyarakat yang posisinya ada di bawah. Dikarenakan memang belum ada suatu kesadaran rakyat, akan pentingnya budaya (culture) demokrasi, terutama dalam arti yang sesungguhnya. Tidak lain semua tersebut terjadi disebabkan oleh karena rendahnya akan pengetahuan tentang nilai-nilai (budaya) demokrasi yang selanjutnya menjadi dasar untuk kemudian menjalani kehidupan di negara demokrasi. Kenyataan tersebut, selanjutnya ditambah dengan kurangnya peranan penyelenggara pemilu, dalam mensosialisasikan kepada rakyat akan pentingnya nilai-nilai demokrasi (budaya demokrasi), yang sesungguhnya sangat perlu untuk kemudian dipahami agar nantinya dapat dilaksanakan di lapangan. Dengan demikian, dalam negara dengan bentuknya demokrasi, tidak mungkin dapat dicapai begitu saja, walaupun sebenarnya telah tersedia struktur demokrasi, yang berfungsi sebagai penopang utama prosedur demokrasi. Struktur demokrasi sebagaimana dimaksud di atas, yaitu sebagai berikut. Adanya pemerintah yang bertanggungjawab, suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, suatu organisasi politik (partai politik) yang mencakup lebih dari satu partai politik (dwi partai atau multi partai politik), pers media massa yang bebas dan merdeka untuk menyatakan pendapat dan sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan (Budiardjo,2008;120, Winarno,2009;99). Namun, sesungguhnya demokrasi sangat memerlukan nilai-nilai demokrasi (culture), di samping telah tersedianya lembaga demokrasi (struktur demokrasi). Karena nilai-nilai
I Gusti Ngurah Santika, SPd
564
demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, haruslah disalurkan kembali ke dalam lembaga-lembaga (struktur) demokrasi, agar kemudian dapat terwujud sistem pemerintahan yang benar-benar bersifat demokratis. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka Henry B. Mayo (dalam Syahuri,2004;23, Budiardjo,118-119, Winarno,2009;98) kemudian menyatakan bahwa demokrasi sendiri perlu didasari oleh nilai-nilai positif dan mengandung unsur-unsur moral universal yang tercermin dari; 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict); 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan suatu masyatakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society); 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers); 4. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum (minimum of coercion); 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam suatu masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat kepentingan serta tingkah laku; 6. Menjamin tegaknya keadilan. Namun, jika kemudian kita lihat kembali, ternyata dalam realitasnya hanya dengan berbekal pengetahuan rendah, terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Kemudian terlintas dalam benak pikiran para pemilih ataupun para pendukung pasangan calon kepala daerah, hanyalah soal kalah dan menang, yang selanjutnya dijadikan sebagai prinsip utama dalam pemilu kepala daerah. Dengan hanya berpikiran bahwa nantinya yang akan keluar sebagai pemenang dalam pemilihan umum kepala daerah, adalah calon pasangan yang memang didukung untuk diunggulkannya kemudian. Namun, setelah adanya pengumuman hasil pemilu dari KPUD, ternyata apa yang sebenarnya menjadi harapan utama pendukung calon kepala daerah andalannya tersebut pada saat pemilihan umum. Dalam kenyataannya setelah diumumkan kemudian dinyatakan kalah, yang pastinya akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dari pendukung pasangan calon kepala daerah yang tidak terpilih tersebut. Bahkan tidak jarang masalah inilah kemudian, yang dapat mempropokasi bahkan sebagai penyebab utama bentrokan-bentrokan fisik, yang terjadi selama ini di daerah, khususnya masyarakat di daerah. Ditambah lagi, yang kemudian untuk patut disayangkan pula bahwa elit politik, yang sebelumnya menjadi calon kepala daerah yang dinyatakan kalah, dalam kenyataanya merasa tidak puas dengan hasil pemilu tersebut. Selanjutnya melakukan berbagai aksi, untuk kemudian mempropokasi masyarakat terutama para pendukungnya, dengan menyatakan, bahwa kekalahannya disebabkan oleh kecurangan-kecurangan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
565
lawannya. Dengan demikian, dapat saja memancing kemarahan dari masa pendukung daripada kedua belah pihak, untuk kemudian saling membela. Bahkan, pembelaan tersebut ditunjukan dalam bentuk tindakan-tindakan, yang dapat saja dipandang merupakan suatu tindakan, yang kemudian digolongkan sebagai anarkisme. Dengan demikian, masyarakat seakan-akan berada pada keadaan anomie, yakni keadaan kacau karena tak ada patokan tentang perbuatan-perbuatan apa yang baik dan apa yang tidak baik (Soekanto,2009;214). Dalam buku Soekanto yang lainnya, yaitu Sosiologi Suatu Pengantar (2009;191), yang menyatakan bahwa prilaku yang menyimpang tadi akan terjadi apabila manusia mempunyai kecendrungan untuk lebih mementingkan suatu nilai sosial budaya daripada kaidah-kaidah yang ada untuk mencapai cita-cita tersebut. Pudarnya pegangan pada kaidah-kaidah menimbulkan keadaan yang tidak stabil dan keadaan tanpa kaidah yang oleh Emile Durkheim dinamakan anomie. Padahal untuk menyelesaikan permasalahan, yang menyangkut masalah hasil daripada pemilu kepala daerah dapatlah kemudian diajukan, kepada lembaga yang memang berwenang untuk itu, yaitu Mahkamah Konstitusi (constitutional court). Karena terkait dengan adanya permasalahan tersebut, hanya dapat diselesaikan secara konstitusional, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dan jika masalah tersebut berkaitan dengan adanya pelanggaran pidana, tentunya kemudian dapat diajukan kepada lembaga berwajib, tentunya dalam hal ini adalah kepolisian sebagai lembaga yang berwenang untuk itu. Bahkan dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, jika perkara yang dimohonkan tersebut terkait dengan hasil pemilihan umum, namun dalam kenyataannya ada hubungan dengan pelanggaran hukum, yaitu berupa tindakan yang dapat golongkan sebagai tindak pidana, maka untuk selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Bahkan, apabila kemudian dalam kenyataannya kasus yang ditangani oleh kepolisian, terkait dengan adanya tindak pidana pada saat pemilu, sedemikian besar sehingga dapatlah dikatakan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Maka, untuk selanjutnya Mahkamah Konstitusi, sudah pastinya akan menunda sementara waktu persidangannya, sampai kemudian dengan adanya putusan daripada pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap, terkait dengan kasus pelanggaran pidana dalam pemilu tersebut. Lebih lanjut terkait dengan pemilihan umum bagi kepala daerah, ternyata untuk sekarang, telah ditentukan bahwa tidak hanya partai politik saja yang ikut terlibat untuk memegang peranan utama, seperti sebelumnya dinyatakan dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004. Bahkan, dalam kenyataan dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan pemilihan umum bagi kepala daerah, telah ditentukan pula di
I Gusti Ngurah Santika, SPd
566
sana, bahwa kepala daerah tidak hanya dicalonkan oleh partai politik. Namun, dalam kenyataannya untuk sekarang ini, terkait dengan pencalonan kepala daerah untuk mengikuti pemilu kepala daerah dapat juga secara perorangan, yang berarti tanpa melalui partai politik. Sehingga untuk ke depannya, yang ditentukan untuk dapat menjadi calon pemimpin daerah, adalah benar-benar orang yang kemudian dikenal oleh rakyat, untuk selanjutnya dapat memimpin daerahnya selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, bukan saja orang yang hanya memiliki duit saja dapat menjadi pemimpin daerah, yang memang dikarenakan mampu untuk memberikan uang mahar kepada pimpinan/elit partai politik tersebut. Ketentuan tersebut, sedikit tidaknya telah menggeser peran utama partai politik dalam konteks demokrasi di daerah. Dengan ikutnya calon-calon kepala daerah, yang tidak melalui jalur partai politik, telah memberikan kesempatan untuk lebih banyak pilihan kepada rakyat, agar benar-benar memilih kepala daerah, yang menurutnya memang pantas untuk selanjutnya memimpin daerahnya selama lima tahun ke depan. Tentunya bukan hanya menerima calon-calon kepala daerah, yang sebelumnya disodorkan oleh partai politik saja. Dapatlah kemudian dikatakan, bahwa adanya calon kepala daerah, namun tidak melalui jalur partai politik, merupakan suatu terobosan yang sifatnya sangat mendasar dengan membawa angin perubahan yang benar-benar sangat siginifikan, khususnya terhadap proses demokratisasi yang sedang berlangsung deras di daerah, berkaitan dengan pemilu kepala daerah. Namun, setiap perubahan tentunya membawa konsekuensinya masing-masing, atau akan membawa efek tersendiri, baik yang berbentuk negatif maupun positif. Dapatlah kemudian dikatakan, bahwa dulunya di mana dalam ketentuan berkaitan dengan pemilu kepala daerah, yang diharuskan agar dapat menjadi calon kepala daerah, haruslah direkomendasikan terlebih dahulu oleh partai politik. Maka, dampak negatif yang muncul ketika itu, adalah terjadinya kolusi antara calon kepala daerah dengan pimpinan partai politik/elit politik, khususnya berkaitan dengan rekomendasi untuk dapat menjad calon kepala daerah dari partai politik. Sedangkan untuk sekarang setelah adanya yudicial rivew yang dilakukan oleh MK, berkaitan dengan pencalonan kepala daerah, yang ternyata dalam putusan MK tersebut memberikan kesempatan untuk dapat diikuti oleh perseorangan (individual). Maka, dalam kenyataannya kolusi pun kemudian terjadi antara calon kepala daerah dengan para pemilihnya, yang selanjutnya banyak diistilahkan orang bahwa pagipagi sebelum memilih ternyata ada serangan fajar, namun inilah konsekuensi yang harus kemudian kita terima. Bahkan ada orang berpendapat bahwa dulunya demokrasi yang dianut, adalah demokrasi borongan oleh partai politik dengan calon kepala daerah, sedangkan untuk sekarang, menjadi demokrasi eceran antara calon kepala daerah dengan para pemilih (konstituen). Setidaknya, dengan menoleh masa lalu, berkaitan dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
567
kehidupan demokrasi di negara kita, maka untuk selanjutnya penulis merasa sangat yakin, bahwa masyarakat nantinya dalam menentukan pilihan tentu akan dapat bersikap lebih bijak lagi, dikarenakan dengan semakin meratanya pendidikan seperti sekarang ini. Demokrasi paling tidak, untuk sekarang telah memberikan harapan besar bagi kesejahteraan rakyat, khususnya di daerah. Demokrasi adalah sebuah pilihan, yang memang pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, seperti memberikan kesejahteraan kepada rakyat, yang konsekuen untuk melaksanakannya. Demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sebuah sarana untuk selanjutnya menjadikan rakyat mampu untuk mencapai tujuan yang sebenarnya dinginkannya. Namun, hanya dengan jalan demokrasi itulah kemudian, baru dapat tercapai tujuan rakyat tersebut, yaitu kesejahteraan. Oleh karena demikian, selanjutnya yang ada kaitannya dengan demokrasi, penulis memiliki suatu kesimpulan, bahwa kalau demokrasi tidak dapat menyejahterakan rakyat, maka kita tidak butuh apapun dari demokrasi. Selanjutnya berkenaan hanya dengan dicantumkannya istilah gubernur, bupati dan walikota saja, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun, bagaimana dengan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota, apakah selanjutnya dapat ditiadakan jabatan ini atau apakah perlu untuk diadakan pemilihan dalam satu paket pasangan bersama dengan kepala daerah? Terkait dengan bisa atau tidaknya, untuk kemudian jabatan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota ini ditiadakan, ternyata masih menjadi pertanyaan besar, yang sampai sekarang memang belum bisa dijawab secara pasti. Ketentuan ini tentunya akan berbeda sekali dengan adanya jabatan Wakil Presiden, yang telah ditentukan dengan jelas dalam ketentuan UUD 1945. Sehingga dalam UUD 1945, sudah sangat jelas menentukan bahwa berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan, yang sebelumnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, untuk selanjutnya ditentukan dan dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Berbeda dengan jabatan wakil kepala daerah yang memang tidak ditentukan keberadaannya secara pasti dalam UUD 1945, namun untuk selanjutnya hanya ditentukan dalam undang-undang. dengan demikian ada atau tidaknya jabatan wakil kepala daerah nantinya adalah sangat tergantung daripada kehendak pembentuk undang-undang. Sehingga untuk sekarang ini, berkaitan dengan keberadaan daripada jabatan wakil kepala daerah adalah menyangkut masalah pilihan politik. Dalam pada itu, tentunya akan tergantung pula, pada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya politis, terkait dengan ada atau tidaknya manfaat, yang kemudian diperoleh dengan adanya jabatan wakil kepala daerah. Pendapat tersebut dikatakan, tidak lain dikarenakan selama ini tugasnya yang mungkin bisa dikatakan kurang jelas, sehingga dalam realitasnya hanyalah dijadikan bemper oleh kepala daerah,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
568
seperti yang terlihat untuk sekarang ini. Bahkan karena tugasnya yang kurang jelas tersebut, maka tidak jarang terjadinya konflik kepentingan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, seperti ditengarai dengan adanya rebutan tugas. Selain itu, ditambah lagi dengan adanya usaha untuk memperebutkan pengaruh dari pemilih, dengan tujuan untuk menjadi kepala daerah selanjutnya, hal mana semua itu biasanya terjadi disaat menjelang pikada. Keharmonisan hubungan kepala daerah dengan wakil kepala daerah, hanya terjadi untuk tahun-tahun awal pada periode kepemimpinan mereka. Sedangkan untuk selanjutnya, mereka mengalami konflik berkepanjangan, seperti terlihat akhir-akhir ini dengan semakin banyaknya wakil kepala daerah, yang mengambil keputusan untuk kemudian mengundurkan diri, sebelum habis masa jabatannya. Alasan mundur wakil kepala daerah tersebut, paling banter karena adanya perasaan ketidakcocokan lagi untuk berpasangan dengan kepala daerahnya. Implikasi yang tanpa disadari timbul dari adanya pertentangan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, yaitu secara tidak langsung akan menyebabkan kebingungan di antara aparat pemerintah yang berada di bawahnya. Tidak lain, dikarenakan dengan adanya perpecahan antara kepala daerah dan wakilnya dalam menjalankan pemerinahan daerah, pada akhirnya akan berimplikasi luas terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, untuk ke depannya dapat saja ketentuan berkenaan pemilu kepala daerah, yang untuk sekarang ini, dilakukan secara bersamaan dengan wakil kepala daerah, untuk selanjutnya akan menimbulkan pula berbagai masalah dikemudian hari berkenaan dengan tafsirannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan usulan agar kepala daerah saja yang benar-benar dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilukada. Sedangkan, untuk jabatan wakil kepala daerah dapatlah selanjutnya dipilih dan ditentukan oleh DPRD. Namun, disertai dengan adanya ketentuan lain, bahwa calon wakil kepala daerah sebagaimana dimaksudkan di atas, haruslah dicalonkan sendiri oleh kepala daerah yang terpilih sebelumnya. Sehingga diharapkan wakil kepala daerah yang terpilih nantinya benar-benar mampu, untuk kemudian mengikuti semua perintah dari kepala daerah yang sebelumnya mencalonkannya sebagai wakil kepala daerah. Bukan berarti dengan adanya ketentuan berupa pemilihan oleh DPRD terkait jabatan wakil kepala daerah, maka dengan demikian legitimasinya menjadi lemah. Dikarenakan sebenarnya wakil kepala daerah tersebut, tentunya juga memiliki legitimasi yang kuat, dikarenakan dipilih dan ditentukan oleh rakyat, namun dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui wakilwakilnya di DPRD. Dan dalam kenyataannya, jika untuk selanjutnya memang rakyat merasa, bahwa dengan tidak dicantumkannya secara tegas, berupa ketentuan yang mengatur tentang jabatan wakil kepala daerah di dalam UUD 1945, kemudian hanya dicantumkan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
569
dalam UU saja, sehingga tugas yang dimilikinya tidak jelas. Bahkan menyebabkan hanya pemborosan saja terhadap APBD, maka berkaitan dengan adanya masalah tersebut, penulis berpendapat bahwa untuk penafsirannya dapat saja diajukan ke MK, untuk selanjutnya mendapatkan keputusan yang bersifat final dan mengikat, berkenaan dengan penafsiran konstitusional, terutama berkaitan dengan keberadaan jabatan wakil kepala daerah dalam UUD 1945. Karena memang pada hakekatnya berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas atas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, adalah kewenangan yang sebenarnya bersifat melekat pada Mahkamah Konstitusi (constitutional court), yang memang bertugas untuk menjaga konstitusi (guardian of the constitutiton). Hal mana adalah sangat sesuai dengan pendapat dari Simanungkalit (2004;14) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa semangat yang terpenting dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip konstitusionalitas bahwa segala sesuatu, harus diselesaikan menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Wilayah Negara. Berkaitan dengan wilayah negara, untuk sekarang ini telah dipertegas kembali berupa pengaturannya dalam ketentuan UUD 1945. Khusus untuk itu telah ditentukan dalam Bab IXA, terutama ketentuan Pasal 25E UUD 1945 telah diatur pula mengenai batas-batas wilayah negara Indonesia dan hak-haknya, yang kesemuanya tersebut ditetapkan kembali dengan bentuk undang-undang. Kemudian ketentuan inilah yang dijadikan landasan dasar wawasan nusantara bagi Indonesia, terkait dengan wilayah negara Indonesia, yang di dalamnya terdiri dari beribu-ribu pulau, yang dihubungkan oleh perairan Indonesia. Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai diri dan lingkungannya, yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Sebenarnya sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, dalam kenyataannya sudah ada ketentuan yang pada dasar mengatur berkaitan dengan wilayah Indonesia, hanya saja kemudian berbagai peraturan yang dimaksud tersebut telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Mahmud MD,2009;225-227). Adapun yang berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan batas wilayah negara Indonesia adalah:
I Gusti Ngurah Santika, SPd
570
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka. 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. 3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua Nugini. 4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Garis Batas Laut Kedua Negara di Selat Singapura. 5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 6. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on the law of the sea (UNCLOS). 7. Undang-Undang No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. 8. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 9. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 10. Undang-Undang No. 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan. 11. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 13. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. 14. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. 15. Keppres No. 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis-Garis Landas Kontinen Antara Kedua Negara. 16. Keppres No. 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealt Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu. 17. Keppres No. 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Lantas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan Selat Andaman.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
571
18. Keppres No. 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah Laut Timur dan Laut Arafuru. 19. Keppres No. 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara. 20. Keppres No. 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Sumatra Hindia. 21. Keppres No. 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman. 22. Keppres No. 81 Tahun 1982 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-Batas Maritim Antara RI dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini Kemudian dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, khususnya pada perubahan ketiga ternyata ditetapkannya wilayah negara Indonesia dalam UUD 1945, yang kemudian tercantum secara tegas dalam ketentuan Pasal 25E, yang pada intinya menyatakan bahwa pengaturan terkait wilayah Indonesia akan ditetapkan selanjutnya dalam bentuk undang-undang. Apakah sesudah dicantumkannya ketentuan yang ada kaitannya dengan wilayah negara Indonesia dalam konstitusi, maka masalah yang berkaitan dengan wilayah negara Indonesia akan selesai begitu saja? Tentu kiranya berkaitan dengan wilayah negara, tidaklah mungkin dapat diselesaikan hanya dalam realitasnya mencantumkan ketentuan tersebut dalam konstitusi, hal mana pada dasar konstitusi merupakan norma dasar. Bahkan dalam konstitusi pun, pengaturan yang berkaitan dengan batas wilayah negara Indonesia, dalam kenyataannya masih perlu untuk didelegasikan kembali terutama dalam bentuk peraturan yang ada di bawahnya, yakni undang-undang. Menurut pendapat penulis, mengenai batas wilayah negara, tidak mungkin hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang saja. Apalagi untuk ketentuan Pasal 25E UUD 1945 tersebut, terkesan sangat subjektif sifatnya, karena menyangkut wilayah negara hanya akan diatur kembali oleh lembaga eksekutif dan legislatif dengan bentuk undang-undang. Dengan demikian, kita tahu bahwa undang-undang adalah merupakan kehendak negara, karena memang pada
I Gusti Ngurah Santika, SPd
572
dasarnya dibentuk melalui alat perlengkapan negara. Apakah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara seperti ditentukan oleh Konstitusi, yaitu antara Presiden dan DPR yang sebenarnya bersifat sepihak dalam bentuk undang-undang, khususnya berkaitan dengan wilayah negara Indonesia dapat mengikat negara lain. Atau dengan pernyataan lain, dapatkah kemudian undang-undang tersebut memaksakan kehendaknya kepada negara lainnya, yang mungkin ditinjau dari segi internasional, sebenarnya juga sama-sama memiliki kedaulatan khususnya berkaitan dengan wilayah negaranya, terutama yang tentunya berbatasan secara langsung dengan wilayah negara Indonesia? Dalam pada itu, penulis sesungguhnya masih meragukan kekuatan dari argumentasi yang mendasari adanya ketentuan Pasal 25E UUD 1945. Dikarenakan, sebenarnya dalam teorinya telah ditentukan berlakunya suatu hukum, baik yang dalam bentuk konstitusi maupun undang-undang, hanya terbatas pada daerah tempat hukum tersebut dibuat dan berada (territorial). Yang berarti, jika seandainya sudah memasuki wilayah hukum negara lainnya, maka validitas hukum tersebut sesungguhnya tidaklah berlaku lagi, karena dalam kenyataannya sudah tidak lagi berada di bawah kedaulatan negara di tempat hukum tersebut terbentuk. Begitupun mengenai wilayah negara Indonesia, yang pada hakekatnya dikelilingi oleh wilayah negara-negara lainnya, sehingga untuk itu secara otomatis akan selalu berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Dengan demikian, secara tidak langsung sebenarnya berkaitan dengan pengaturan wilayah suatu negara, tentunya memerlukan bentuk partisipasi serta keterlibatan dari negara lain. Hal tersebut, pada dasarnya merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bertetangga yang baik antar negara lainnya dalam hubungan internasional. Pemikiran tersebut tentunya memiliki alasan cukup kuat, tidak lain dikarenakan negara-negara tetangga, yang juga secara langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia, tentunya memiliki kepentingan secara langsung dengan negara Indonesia di dalam menetapkan batas-batas wilayah negaranya tersebut. Dengan demikian, berkaitan dengan pengaturan wilayah negara, seharusnya tidaklah hanya mengandalkan kekuatan undang-undang, yang sebenarnya jika ditinjau dai sudut keberlakuannya, hanyalah dapat berlaku ke dalam wilayah negara saja (internal). Namun, juga tentunya harus didasari oleh suatu kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia di satu pihak dengan pemerintah negara tetangga di lain pihak. Kesepakatan bersama tersebut, dapat saja dalam bentuk perjanjian Internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara tetangga, yang wilayahnya berbatasan secara langsung dengan wilayah negara Indonesia. Oleh karena itulah, penulis berpendapat demikian terhadap ketentuan Pasal 25E UUD 1945, khususnya pengaturan wilayah negara yang kemudian ditegaskan kembali untuk ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, UU yang dibuat oleh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
573
Indonesia seolah-olah terlihat seperti kehendak yang bersifat sepihak dari Indonesia di dalam menetapkan batas-batas wilayah negara. Di mana sebenarnya berkaitan dengan penetapan wilayah negara, tidak hanya menyangkut satu wilayah negara saja. Melainkan dalam kenyataannya akan selalu melibatkan negara-negara tetangga, yang tentu saja memiliki berbagai kepentingan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, terhadap penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia. Setelah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, memang dalam kenyataannya, berkaitan dengan wilayah negara Indonesia dalam sejarahnya pernah mempraktekkan pernyataan sepihak dari pemerintahan terhadap kedaulatan wilayah negara Indonesia. Lebih lanjut untuk memperkuat argumen daripada penulis tersebut di atas, maka berdasarkan hal tersebut dipandang perlu kemudian, untuk dikutipkan beberapa pendapat dari para ahli. Namun, pendapat para ahli tersebut merupakan suatu pendapat yang ada kaitannya dengan wilayah negara, di mana pada dasarnya pendapat para ahli tersebut, adalah sesuai dengan apa yang kemudian oleh penulis maksudkan seperti tersebut di atas. Berkaitan dengan adanya pernyataan wilayah negara yang bersifat sepihak, Kusumaatmadja (2003;1) menyatakan bahwa dalam rangka tinjauan tadi baik Deklarasi 13 Desember 1957, maupun Undang-Undang Nomor 4 Prp.Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia demikian pula Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Februari 1969, semuanya merupakan tindakan sepihak (unilateral) Indonesia. Begitupun, untuk selanjutnya menurut penulis bahwa UUD 1945, khususnya dengan ketentuan Pasal 25E, yang pada dasarnya memandang masalah batas wilayah negara, terlihat hanya ditentukan sendiri secara sepihak oleh Indonesia dengan bentuk undang-undang. Padahal kita ketahui bahwa undang-undang itu sendiri sebenarnya hanyalah bentuk hukum yang bersifat mengikat ke dalam, tetapi penulis masih ragukan, apakah undang-undang tersebut yang nyatanya dibuat sepihak mengenai batasbatas wilayah negara dapat mengikat ke luar? Jika memang kemudian mengikat, apakah yang menjadi dasarnya atau jika tidak mengikat apakah yang menyebabkannya? Pada hakekatnya suatu undang-undang yang berkaitan atau menyangkut batas-batas wilayah negara lain, maka untuk itu dipandang perlu kembali diatur dalam bentuk perjanjian internasional. Dalam pada itu, terkait pengaturan wilayah negara dengan suatu perjanjian internasional, mungkin dapat saja nantinya ditransformasikan kembali dalam bentuk peraturan perundang-undangan di dalam negara tersebut. Maksud daripada transformasi perjanjian internasional tersebut ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti apa yang dimaksudkan di atas, bertujuan agar nantinya peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya memiliki kekuatan mengikat ke dalam negara (internal), melainkan juga dalam kenyataannya memiliki kekuatan yang mampu mengikat ke luar negara
I Gusti Ngurah Santika, SPd
574
tersebut. Dikarenakan jika suatu undang-undang yang di dalamnya mengatur berkaitan dengan wilayah negara, yang tentunya memiliki hubungan dengan wilayah negara lain, namun tidak dibuat berdasarkan perjanjian internasional. Berkaitan dengan keberlakuan undang-undang tersebut dapatlah kemudian untuk dipastikan, tidak akan memiliki kekuatan mengikat (daya lakunya) secara hukum internasional. Jika memang dalam kenyataannya tanpa didahului oleh adanya suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, untuk selanjutnya menyepakati masalah apa saja yang kemudian perlu untuk diatur kembali dalam bentuk perjanjian internasional, sehingga selanjutnya akan mengikat negara-negara yang membuat perjanjian tersebut. Misalkan, dapat saja suatu negara menentukan tentang batas-batas wilayah negaranya, hanya dengan suatu pernyataan sepihak lewat bentuk undang-undang mungkin nantinya dapat diterima. Fenomena tersebut merupakan suatu bentuk kekecualian yang mungkin bisa terjadi bilamana dalam kenyataannya kemudian, ada pernyataan susulan berupa penerimaan bersama dari dunia internasional, seperti Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Bahkan, dapatlah kemudian dikutipkan isi dari Deklarasi Juanda, yang membuktikan lebih tegas lagi tentang suatu pernyataan bersifat sepihak, yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pemerintah pada waktu itu, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pendirian Pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Februari 1958 di Jenewa (Prodjodikoro,1984;17) (kursif dari penulis). Terlihat jelas bahwa isi dalam Deklarasi tersebut, walaupun pada dasarnya merupakan pernyataan yang memang bersifat sepihak, namun tetap saja di dalam isi deklarasi tersebut terdapat perkataan akan diperhatikan dalam konferensi internasional yang sebenarnya memiliki makna berkaitan dengan pengaturan wilayah suatu negara, perlu pula untuk mendapatkan kesepakatan bersama dengan negara-negara lainnya, karena masalah penetapan batas wilayah negara tidaklah mungkin dapat dilakukan sendirian. Tentu dengan adanya pernyataan sepihak dari pemerintah di atas, kemudian untuk mendapatkan legitimasi dari dunia internasional dalam bentuk dukungan, tentu untuk ke depannya diperlukan suatu perundingan-perundingan lanjutan, yang berkaitan dengan adanya pernyataan sepihak dari pemerintah tersebut di atas. Sehingga dengan dilakukan hal demikian, menjadi sempurnalah deklarasi yang dahulunya merupakan sekedar, untuk kemudian memberi bentuk pada pernyataan yang sifatnya hanya sepihak. Bahkan notabene deklarasi tersebut menurut penulis hanyalah memiliki kekuatan mengikat ke dalam negara tersebut. Kemudian untuk selanjutnya menjadi berlaku dan tentunya mengikat ke luar negara, karena memang sudah mendapatkan penerimaan dari negara-negara lainnya. Oleh karena itu, untuk membuat ketentuan dalam bentuk undang-undang, khususnya berkaitan dengan wilayah negara, harus pula
I Gusti Ngurah Santika, SPd
575
memperhatikan keadaan di negara lainnya. Untuk memperkuat pendapat penulis tersebut di atas perlu dinyatakan bahwa faktor-faktor di negara lainnya, ternyata memiliki peranan yang cukup penting dalam rangka untuk membantu membentuk hukum nasional. Maka berkaitan dengan pernyataan tersebut di atas, dapatlah dikemukakan pendapat dari Sunaryati Hartono dalam Syaukani dan Thohari (2010;33) yang menyatakan bahwa faktorfaktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang yang kita cita-citakan atau tergantung kepada kehendak pembentuk hukum, praktisi, atau teoritisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Sehingga berkaitan dengan batas wilayah negara, tentunya tidaklah mungkin dapat dilepaskan antara satu negara dengan negara lainnya. Maka untuk itu, perlulah kemudian agar selalu memperhatikan kepentingan negara-negara tetangga, baik yang nantinya akan ditetapkan melalui perjanjian internasional, sehingga akan mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Hal mana memang seharusnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari hukum internasional, adalah sangat berbahaya jika dalam kenyataannya kemudian, setiap negara menentukan sendiri-sendiri batas-batas wilayahnya sekehendak hatinya. Dikarenakan akan berakibat pula terhadap kacaunya ketertiban hukum internasional. Dengan terjadinya peristiwa demikian, dapatlah dipastikan bahwa negara-negara yang besar (adidaya), karena memiliki kekuatan persenjataan kuat yang kemudian dapat memenangkan pertarungan berkaitan dengan batas wilayah negara, dan tentunya hal ini sangat tidak menguntungkan bagi negara kita untuk sekarang ini. Sedangkan dilain pihak, untuk negara-negara kecil selalu ingin mengadakan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangganya yang besar, agar tidak diusik kedaulatannya. Jadi, negara-negara kecil akan selalu berkepentingan untuk memelihara hubungan baik dengan tetangganya, agar kemerdekaannya tetap dihormati (Budiardjo,2008;51). Jadi menurut pendapat penulis ketentuan Pasal 25E UUD 1945, pada dasar merupakan suatu pengaturan yang sifatnya terlalu menyederhanakan, berkaitan dengan penetapan batas-batas wilayah negara, yang jika ditelusuri lebih lanjut sebenarnya memerlukan kerja sama internasional antara negara-negara yang berkepentingan. Apalagi menurut ketentuan hukum internasional yang berdasarkan pada prinsip the sovereign equlity of nation, semua negara sama martabatnya. Menurut penulis, keluarnya ketentuan ini adalah akibat adanya trauma mendalam dari para anggota MPR, berkenaan dengan peristiwa terlepasnya timor-timur dari wilayah NKRI. Sehingga menyebabkan anggota MPR beramai-ramai, untuk membuat satu ketentuan yang nantinya dapat diharapkan melindungi wilayah NKRI dari disintegrasi. Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis berpendapat mengenai batas wilayah negara, seharusnya diselesaikan kemudian dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
576
suatu perjanjian yang tentunya bersifat internasional. Seperti dalam bentuk perjanjian bilateral mengenai pengaturan batas-batas wilayah negara antar dua negara, maupun dalam bentuk pernjanjian multilateral, karena memang menyangkut banyak negara di dalamnya, misalnya berkaitan dengan pengaturan pelayaran lintas damai. Sehingga untuk itu, tidak hanya Indonesia sendiri yang kemudian menentukan batas-batas wilayah negaranya dan menjadikan wilayah tersebut kemudian di bawah kedaulatannya. Namun, juga perlu kiranya bagi pihak-pihak lain (negara-negara) yang memiliki kepentingan terhadap penetapan batas-batas wilayah negara Indonesia tersebut, untuk diikut sertakan kemudian dalam suatu perjanjian yang berskala internasional, dengan harapan agar nantinya kepentingankepentingan negara lainnya benar-benar tidak dirugikan dengan adanya tindakan berupa penetapan batas wilayah negara oleh Indonesia. Pendapat penulis sebagaimana dimaksudkan di atas, diperkuat kembali oleh Arsana (2007;23) dengan mengemukakan satu contoh berkaitan dengan praktek dalam hukum internasional, khususnya berkaitan dengan adanya penetapan wilayah negara. Menurutnya, bahwa dengan dikuasainya Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia melalui keputusan Court of Justisce (ICJ) dengan kemenangan atas IndonesiaDengan kata, lain Indonesia harus melakukan revisi terhadap PP 38/2002(kursif penulis). Artinya untuk sekarang, kita tidak mungkin dapat secara sepihak untuk menetapkan batas-batas wilayah negara, tanpa adanya suatu perjanjian mendahuluinya yang dibuat antara negara tetangga. Perjanjian internasional tersebut dibuat oleh negara tetangga, karena dalam kenyataannya berbatasan dengan wilayah negara Indonesia, ataupun dengan negara-negara lainnya dapat saja dilakukan, karena negara lain memiliki kepentingan secara tidak langsung terhadap adanya penetapan batas wilayah negara oleh Indonesia. Bukan maksud penulis, untuk mengatakan bahwa kita harus mengikuti begitu saja, apa yang kemudian menjadi kebiasaan internasional untuk selanjutnya hukum tersebut, selanjutnya kita telan dan terapkan secara mentah-mentah di Indonesia. Bukan juga, bermaksud bahwa penulis untuk menganut ajaran yang mengatakan bahwa hukum internasional adalah lebih tinggi kedudukannya daripada hukum nasional (primat internasional). Namun, ada kalanya yang menyangkut kedaulatan suatu negara, berkenaan dengan penetapan batas-batas wilayah suatu negara sebagai salah satu unsur negara untuk dapat berdirinya suatu negara, tidak mungkin dapat dikatakan hanya menyangkut satu wilayah negara saja. Hal ini dikarenakan, bahwa kedaulatan suatu negara dengan sendirinya akan berakhir, jika sudah dimulai kemudian dengan kedaulatan negara lain atau menyentuh batas wilayah negara lain, setidaknya berbatasan langsung dengan negara lain. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa menyangkut batas-batas wilayah negara Indonesia, untuk sekarang ini, tidaklah hanya dapat untuk dinyatakan secara
I Gusti Ngurah Santika, SPd
577
sepihak. Apalagi keadaan negara Indonesia yang seperti sekarang ini, bukanlah tindakan yang tepat untuk dilakukan, karena ini merupakan pernyataan bersifat sepihak, sehingga bukan hanya menyangkut dalam bidang hukum saja. Karena nantinya akan dipengaruhi oleh pula oleh kekuatan politik internasional, yang selanjutnya akan menentukan keputusannya, apakah mendukung atau tidaknya terhadap tindakan negara tersebut. Apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan benar-benar sesuai dengan sumber-sumber hukum internasional yang berlaku, dalam hubungannya dengan negara-negara lainnya. Bahkan, dalam ketentuan Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional (dalam Bisri,2010;91-92) yang selanjutnya menyebutkan sumber hukum internasional secara formal, yaitu treaty atau traktat atau International Convention, Kebiasaan Internasional atau International Custom, Prinsip Hukum Umum atau General Principles of Law, Yurisprudensi Internasional dan Doktrin Hukum Internasional. Lebih lanjut terkait dengan pengaturan batas wilayah negara yang sebenarnya tidaklah perlu untuk dicantumkan dalam undang-undang dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, Joeniarto (1996;20) kemudian menyatakan bahwa tidak dimasukannya soal batas daerah negara di dalam undang-undang dasar negara dapat dimengerti, sebab penentuan batasbatas negara itu tidaklah ditentukan dengan secara sepihak saja. Soal batas negara adalah soal perjuangan, entah itu dilakukan dengan secara perjanjian internasional atau dengan secara kekuatan senjata. Mengenai batas wilayah itu orang tidak dapat melihat dalam undang-undang dasar negara, tapi merupakan ketentuan dalam perjanjian (taktat) antara dua negara atau lebih yang berkepentingan dan biasanya merupakan negara tetangga (Kusnardi dan Sarigih,2008;106). Lebih lanjut menurutnya bahwa apabila suatu perjanjian dibuat hanya oleh dua negara saja maka disebut perjanjian bilateral, sedangkan jika suatu perjanjian dibuat lebih dari dua negara maka perjanjian itu disebut perjanjian multilateral. Jika kata-kata mengenai batas-batas wilayah negara, dalam kenyataannya disebutkan dalam undang-undang dasar, maka dapat kemudian dikatakan bahwa ketentuan tersebut sebenarnya tidaklah memiliki makna secara yuridis untuk dapat mengikat, apalagi dipandang dari hukum internasional. Oleh karena itu, penentuan berkaitan dengan pengaturan batas wilayah negara, tidak mungkin dapat kemudian ditentukan secara sepihak oleh suatu negara. Seperti apa yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa berkaitan dengan pengaturan batas-batas wilayah negara negara, tidaklah dapat untuk kemudian diputuskan secara sendiri-sendiri oleh suatu negara, karena secara tidak langsung penentuan batasbatas wilayah negara, tentunya juga berkaitan dengan wilayah negara lain. Sehingga, apa yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Joeniarto maupun Kusnardi dan Sarigih, kemudian dapat penulis setujui sepenuhnya. Bahkan konsekuensinya yang mungkin timbul, karena
I Gusti Ngurah Santika, SPd
578
adanya penempatan pasal yang mengatur wilayah suatu negara dalam konstitusi, namun hanya dengan ditentukan secara sepihak, khususnya dalam bentuk undang-undang, tentunya mungkin hanya dapat mengikat ke dalam negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan suatu kekuatan mengikatnya suatu peraturan di dalam dunia internasional, tentunya kita harus menengok kembali sumber-sumber hukum internasional, yang memang pada dasarnya mengikat subjek-subjek hukum internasional. Bahkan menurut penulis, berkaitan dengan adanya ketentuan Pasal 25E UUD 1945, tidak perlu untuk kemudian dicantumkan dalam UUD 1945, hal mana dikarenakan dalam kenyataannya sudah ada ketentuan Pasal 11 UUD 1945, tentang Perjanjian Internasional. Jadi, nantinya berkaitan dengan wilayah suatu negara terkait pengaturan tentang batas-batasnya, akan ditentukan kembali dalam suatu perjanjian antara negara-negara lainnya yang berbatasan secara langsung dengan wilayah negara Indonesia. Disebabkan terkait dengan pengaturan wilayah negara merupakan suatu masalah, bahkan menimbulkan suatu akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Oleh karena itu, perlulah untuk dibuat suatu perjanjian dengan negara lain, berkaitan dengan batas wilayah negara Indonesia, yang berarti dibuat oleh kedua atau lebih dari pemerintah berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap adanya pengaturan berupa penetapan batas wilayah negara oleh Indonesia. Namun, untuk kasus di Indonesia, maka untuk itu diperlukan persetujuan dari DPR, setelah itu barulah kemudian dituangkan kembali dalam bentuk undang-undang, yang merupakan hasil dari diratifikasi perjanjian internasional tersebut. Dengan demikian, barulah pengaturan mengenai penetapan batas-batas wilayah negara akan memiliki kekuatan mengikat baik keluar maupun ke dalam. Tidak lain, disebabkan oleh karena undang-undang tersebut merupakan hasil kesepakatan antara negara lain, yang telah tuangkan dalam bentuk perjanjian internasional. Jadi, dapat dikatakan bahwa bentuk formal daripada mengikatnya undang-undang yang telah diratifikasi oleh Presiden dan DPR, sudah dapat dipastikan keberlakuannya kemudian, baik secara nasional (internal) maupun internasional (eksternal). Untuk, lebih mengetahui mengapa MPR mencantumkan ketentuan ini dalam Perubahan Kedua UUD 1945, maka untuk itu penulis akan mengutip pendapat Asshiddiqie (2005;93), yang menyatakan bahwa karena ada pengalaman pahit berkenaan dengan lepasnya provinsi Timor-Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikalangan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat berkembang keinginan kuat untuk memasukan ketentuan mengenai batas wilayah dalam Undang-Undang Dasar. Sebenarnya jauh sebelum adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada saat sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berkaitan dengan batas-batas wilayah negara, yang memang pada waktu itu, ada usul untuk selanjutnya memasukan daerah ke
I Gusti Ngurah Santika, SPd
579
dalam konstitusi, khususnya berkaitan dengan penetapan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, usul mengenai dimasukannya batas wilayah negara Indonesia akhirnya tidak disetujui, untuk kemudian dimasukan ke dalam undang-undang dasar. Bung Karno mengemukakan pendapatnya bahwa hendaknya dijadikan sebagai daerah negara akan meliputi batas Hindia Belanda dahulu. Selain pernyataan tersebut, dikemukakan pula sebelumnya bahwa di dalam undang-undang dasar modern, tidak perlu dimasukan di dalam soal (batas) daerah negara. usul Bung Karno tersebut ternyata diterima rapat (Joeniarto,1996;20). Untuk lebih jelasnya, berkaitan dengan pernyataan Soekarno pada saat PPKI bersidang, khususnya saat membahas berkaitan dengan pengaturan batasbatas wilayah negara Indonesia, yang pada waktu ada usul untuk dicantumkan kemudian dalam UUD 1945, maka beliau menjawab bahwa. Dalam undang-undang dasar yang modern, daerah tidak masuk. Kami beritahukan kepada Terauttji Kakka, bahwa negara Indonesia akan meliputi batas Hindia-Belanda dahulu. Kecuali dari itu hal daerah itu tidak perlu masuk dalam undang-undang dasar (Setneg,1995;429). Bahkan jika kita cermati kembali dengan saksama, seperti apa yang pernah penulis nyatakan di atas, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 25E UUD 1945 sebenarnya tidak perlu ada. Dikarenakan, kita dapat melihat kembali dalam ketentuan Pasal 11 UUD 1945, tentang Perjanjian Internasional, dikarenakan di dalamnya juga mengatur masalah berkaitan dengan wilayah negara. Bahkan, hal tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa berkaitan dengan batas wilayah negara akan diselesaikan dengan perjanjian internasional, yang tentu selanjutnya akan diratifikasi kembali dalam bentuk undang-undang oleh DPR. Agar bisa mengetahui lebih lengkap lagi bunyinya, maka dapatlah kemudian dilihat kembali dalam ketentuan Pasal 10 UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu berkaitan dengan pengesahan perjanjian internasional dilakukan dalam bentuk undang undang apabila berkenaan dengan : 1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; 2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; 3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara; 4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 5. Pembentukan kaidah hukum baru; 6. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri (kursif penulis). Maka untuk itu, penulis memiliki pendapat bahwa untuk memperkuat ketahanan nasional ke depannya, adalah bagaimana caranya mengefektifkan wilayah-wilayah perbatasan negara, yaitu dengan cara memperhatikan segenap penduduk yang ada di dekat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
580
perbatasan tersebut, supaya untuk selanjutnya ikut pula berpartisipasi dalam menjaga batasbatas wilayah NKRI. Cara yang mungkin dapat digunakan tidak lain adalah dengan pendekatan kesejahteraan, sehingga penduduk yang ada di daerah perbatasan wilayah Indonesia, tidak merasakan bahwa negeri orang sebagai negerinya sendiri, dikarenakan dalam kenyataannya bahwa segala kebutuhannya mungkin dapat dipenuhi hanya apabila kemudian dia pergi ke negara tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan sedemikian rupa, maka penulis rasa mereka nantinya akan tetap merasa sebagai bagian daripada NKRI, yang tentu pada gilirannya akan mampu untuk membangkitkan rasa cinta terhadap bangsa (nationalism), sehingga ikut pula berpartisipasi dalam menjaga wilayah perbatasan NKRI, dengan tujuan agar NKRI tetap utuh. Sehingga apa yang sebelumnya diamanatkan oleh ketentuan Pasal 27 dan ketentuan Pasal 30 UUD 194,5 dapat benar-benar terealisasikan di lapangan, karena memang dimengerti dan sungguh-sungguh dapat dipahami kemudian oleh rakyat sendiri. Pancasila Sebagai Lambang Negara. Terkait dengan amandemen kedua UUD 1945, menurut pendapat penulis terjadi permasalahan sangat serius, khususnya berkaitan dengan lambang negara Indonesia, yang kemudian dinyatakan dalam ketentuan Pasal 36A UUD 1945, bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan tersebut merupakan suatu kekeliruan yang mendasar, terutama dikarenakan di dalamnya menyebut-nyebut nama Pancasila, bahkan diletakan kemudian pada suatu pasal tertentu dalam UUD 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut, tentunya akan mengkibatkan bahwa berkaitan dengan pasal tersebut dikemudian hari dapat saja dijadikan objek perubahan sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Dan seandainya saja nantinya pasal tersebut benar-benar kemudian dirubah, maka lambang negara tersebut tentu selanjutnya akan hilang dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga secara tidak langsung akan merendahkan pula nilai simbolis dari Pancasila itu sendiri, yang sebenarnya sudah dari dahulu diketahui secara implisit oleh rakyat tanpa disebutkan namanya, yang memang tercantum dalam alenia ke empat Pembukaan UUD 1945. Adanya ketentuan Pasal 36A UUD 1945, pada dasarnya telah melanggar isi dari kesepakatan awal sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945, bahwa MPR menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945, dikarenakan di dalamnya Pembukaan UUD 1945 terdapat Pancasila. Memang MPR tidak merubah Pembukaan, namun secara tidak sengaja telah memasukan nama dari
I Gusti Ngurah Santika, SPd
581
bagian isi Pembukaan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Padahal kita tahu bahwa Pancasila yang menurut Nawiasky bagi suatu negara sebaiknya disebut Norma Fundamental Negara (Staasfundamentalnorm) yang menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum tersebut, serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma dimaksud (Attamimi,1992;70). Dengan kata lain, bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara (filosopische gronslag) dari negara yangdidirikan (Supriatnoko,2008;19). Terutama dalam rangka untuk mewujudkan Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber hukum (Santika,2012;6). Hal mana pengertian Pancasila tentunya akan berbeda dengan pengertian sumber hukum, yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata (Kansil dan Christine,2002;19), tidak lain dikarenakan Pancasila bukanlah sebuah norma hukum, melainkan sebagai jiwa dari norma hukum tersebut. Oleh Notonagoro (1982;25) Pancasila merupakan norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu, dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan lain perkataan dengan jalan hukum tidak lagi dapat dirubah. Bahkan menurut Hans Nawiasky, isi Staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (staatverfassung), termasuk norma pengubahnya. Hakikat hukum suatu Staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar (Indrati,2007;46). Pancasila sendiri merupakan cita hukum (rechtsidee). Dengan demikian, banyak istilah yang kemudian diberikan kepada Pancasila, seperti Pokok Kaidah Fundamentil Negara, Norma Pertama, Norma Fundamental Negara. Jadi, pada dasarnya dengan memasukan nama Pancasila dari Pembukaan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal, akan tentunya berakibat, sama pula dengan menjadikan Pancasila sebagai salah satu objek yang mungkin dapat untuk diamandemen nantinya oleh MPR. Jika seandainya suatu hari nanti MPR benar-benar berkehendak untuk mengubah PasalPasal UUD 1945, hal mana tentunya sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945. Seharusnya penyebutan nama Pancasila merupakan suatu konvensi dalam ketatanegaraan, karena pada dasarnya memang telah diterima serta diakui kedudukannya sebagai dasar negara tanpa perlu kemudian mencantumkannya kembali dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila seperti hubungan dasar tak tertulis banyak terdapat dalam sistem konstitusional negara Inggris yang sudah terkenal dengan kata istilah convention (Purbopranoto,1991;213). Apa yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
582
akan terjadi jika saja dikemudian hari ternyata suatu lambang negara, yang dengan tegas di dalamnya menyebut-nyebut nama Pancasila, selanjutnya dirubah oleh MPR, berdasarkan kewenangannya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 37 UUD 1945. Walaupun penulis akui, bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan yang pragmatis. Kelemahan dari ketentuan tersebut, di tambah kemudian dengan adanya kata lambang negara, yang seharusnya bukan Garuda Pancasila melainkan Burung Garuda. Hal ini menurut Abbdurrahman (2009;119) dikarenakan pandangan hidup bangsa Indonesia tersebut dilambangkan dalam bentuk burung garuda (kursif penulis) yang berkalung perisai Pancasila dan di antara kedua kakinya tertulis semboyan Bhineka Tunggal Ika. Artinya di sini terjadi suatu kekeliruan daripada anggota MPR dalam memahami makna berkaitan dengan lambang negara. Jika, dikatakan tentang lambang seharusnya namanya burung garuda, tentunya kemudian tanpa menyebut-nyebut nama Pancasila, karena pada dasarnya yang ditanyakan bukanlah tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Melainkan yang ditanyakan selanjutnya dalam hal tersebut adalah mengenai lambang negara, yaitu burung garuda. Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Dalam UUD 1945. Perubahan Kedua UUD 1945 telah membawa dampak yang lebih baik, bahkan memberikan angin segar terutama terhadap jaminan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk juga berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia. Dalam pada itu adalah selaras dengan tujuan daripada gerakan reformasi yang dilakukan selama ini di Indonesia. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menujungjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (lihat Penjelasan Atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bagian Umum). Dapatlah diketahui sebelumnya bahwa berkaitan dengan ketentuan hak-hak asasi manusia, dalam kenyataannya hanya mendapatkan pengaturan satu pasal saja, yaitu dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945, ketentuan yang berkaitan dengan menyampaikan pendapat itu pun, nanti akan diatur kembali dalam bentuk undang-undang. Jadi, berkaitan dengan adanya jaminan hak asasi manusia dalam bentuk penyampaian pendapat, ternyata konstitusi pada dasarnya hanya memberikan pengaturan yang sebenarnya bersifat semu. Dikarenakan di dalam kenyataannya masih perlu untuk kemudian ditetapkan kembali, tentang apa yang sesungguhnya merupakan konsepsi hak asasi manusia dalam bentuk undang-undang. Tentunya apa yang merupakan hak asasi manusia pada waktu itu, bukanlah hak-hak dasar manusia dalam arti yang sebenarnya, melainkan merupakan hak-hak dasar yang diberikan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
583
oleh DPR dan Presiden dalam bentuk undang-undang. Sehingga, terlihat bahwa hak asasi manusia merupakan belas kasihan daripada DPR dan Pemerintah. Kemudian, dalam kenyataannya barulah kemudian dapat berubah setelah jatuhnya Soeharto, sehingga untuk selanjutnya ditambah dengan memberikan jaminan yang lebih tegas dalam Perubahan UUD 1945, yaitu dengan melakukan beberapa kali amandemen, di samping menyisipkan ketentuan berupa pasal-pasal, yang pada dasar lebih menjamin hak asasi manusia. Besarnya pengaturan berkaitan dengan hak asasi manusia dalam UUD 1945, serta yang berkaitan pula dengan hak-hak warga negara, tentunya disatu sisi merupakan kabar yang sesungguhnya sangat menggembirakan setelah puluhan tahun hak-hak asasi manusia, terpasung dalam kekuasaan penguasa. Kenyataan bahwa di Indonesia pada masa lalu sangat banyak terjadi pelanggaran HAM, yang tidak sedikit di antaranya dilakukan oleh aparat resmi, tentu mengherankan sebab negara ini didirikan di atas prinsip negara hukum (Mahmud MD,2010;140). Namun, untuk itu penulis berpendapat bahwa terkait dengan adanya pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945, tentunya tidak serta merta dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terkait hak asasi manusia dengan begitu saja. Karena tentang pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945, seperti terlihat bahwa berkaitan dengan materinya dalam kenyataannya terdapat pengertian tumpang tindih, khususnya berkaitan dengan pengaturan hak asasi manusia dengan hak warga negara. Karena setahu penulis, berkaitan dengan pengertian hak asasi manusia dengan hak warga negara tentunya tidak sama di antara kedua konsep tersebut di atas. Dikarenakan bahwa untuk pengertian hak asasi manusia, akan sangat berbeda pula dengan pengertian hak warga negara. Berkaitan dengan pengertian hak asasi manusia, maka menurut penulis merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijungjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (lihat UU No. 39 Tahun 1999). Tentunya akan berbeda dengan pengertian hak asasi manusia, jika dalam kenyataannya pengertian yang diberikan adalah sebagai berikut. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan (Gazali dalam Winarno, 2009;129). Tetapi senadainya dibandingkan kembali dengan pengertian tersebut di atas, maka penulis sangat tidak setuju, terkait dengan pengertian hak asasi yang kemudian diberikan oleh Gazali. Karena pengertian hak asasi manusia ternyata dihubungkan dengan konsep kelahiran, seperti adanya kata sejak lahir. Dengan adanya kata tersebut, ternyata hak asasi manusia barulah kemudian ada setelah terlahir ke dunia, yang berarti sebelum lahir
I Gusti Ngurah Santika, SPd
584
tidaklah diakui hak-hak asasinya oleh hukum. Namun, seperti halnya pengertian sebelumnya bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat, jika dengan demikian maka dalam pengertian yang diberikan oleh Gazali adalah menyamakan antara hak-hak dasar dengan kelahiran. Padahal penulis berpendapat bahwa hak asasi manusia, sebenarnya memang sudah ada walaupun sebelum manusia itu lahir ke dunia. Bahkan dalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan hak asasi manusia telah dijamin pula oleh hukum, bahkan sebelum manusia tersebut dilahirkan di dunia. Seperti diakuinya hak untuk mewarisi atau singkatnya hak untuk milik sebagai daripada warisan yang nantinya di dapatkan. Hukum waris sendiri diatur di dalam Buku II KUH Perdata (Bugerlijk recht, privaatrecht). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130. Jaminan hak asasi yang selanjutnya diberikan sebagaimana dimaksud menurut penulis di atas, bahwa seorang bayi yang belum dilahirkan telah ditentukan memiliki hak untuk mewarisi, namun matinya bayi tersebut, maka dianggaplah dia itu tidak pernah ada. Jadi, pada dasarnya hukum sendiri telah memberikan jaminan kepada janin, untuk kemudian memiliki hak mewarisi. Jaminan hukum tersebutlah, yang selanjutnya penulis maksudkan sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, janin telah dianggap sebagai manusia, layaknya seperti manusia yang sudah dilahirkan, bahkan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Namun, tentunya akan berbeda apabila saat dilahirkan kemudian, ternyata dalam keadaan meninggal. Sedangkan berkaitan dengan hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang, dikarenakan telah menyandang hak dan kewajiban dari suatu negara. Dengan pengertian tersebut, tentunya akan jelas perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Dengan demikian, tentunya akan berbeda pula pengertian antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Dikarenakan tentu selanjutnya untuk warga negara akan ada perlakuan-perlakuan yang berbeda dari tempat tinggal dalam suatu negara terutama kepada warga negaranya sendiri, dengan orang lain yang bukan warga negaranya, walaupun pada dasarnya sama-sama memiliki hak asasi manusia. Bahkan, sebenarnya menjadi suatu keharusan bagi suatu negara, untuk kemudian mengadakan pembedaan jelas antara warga negara dengan orang asing yang memang bukan warga negaranya, baik dalam perlakuannya dalam beberapa bidang kehidupan bernegara, walaupun keduanya jelas-jelas memiliki hak asasi manusia (human right) yang tidak berbeda. Tetapi dalam rangka kehidupan bernegara, maka termasuk pula dengan orang asing yang telah masuk dalam suatu negara, tentunya mereka akan tunduk kemudian pada hukum negara tersebut. Semua ketentuan tersebut merupakan bentuk daripada kedaulatan negara, yang tentunya secara
I Gusti Ngurah Santika, SPd
585
tidak langsung akan berakibat mengurangi hak-hak asasi orang asing tersebut. Dengan tegas di sini kita saksikan serangkaian peraturan-peraturan yang diadakan pemerintah untuk lebih membedakan antara warganegara dan orang asing dan untuk memberi perlindungan kepada para warga negara terhadap orang-orang asing dalam bidang perekonomian (Gautama,1977;57). Misalnya mengenai hak asasi dalam bidang kepemilikan tanah di Indonesia, tidaklah kemudian setiap orang berhak untuk selanjutnya memiliki tanah di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya dibatasi kemudian, yaitu hanya untuk warga negara Indonesia saja, yang ditentukan berhak untuk selanjutnya memiliki tanah. Dengan pengertian, bahwa orang asing pun sebenarnya juga memiliki hak asasi manusia khususnya dalam bidang pemilikan, hanya saja untuk kasus di Indonesia, hak-hak asasi terutama dalam bidang pemilikan tanah telah dibatasi sedemikian rupa terhadap orang asing. Sehingga hak pemilikan tanah kepada orang asing, tidak mungkin dapat dilaksanakan kemudian di Indonesia, karena pada dasarnya hukum sendiri telah membatasinya sedemikian rupa. Berkaitan dengan kepemilikan tanah yang kemudian hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. Dapatlah kemudian dikutip dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria yang menyatakan Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik (kursif penulis) (Harsono,1986;11). Terkait dengan adanya pembedaan antara hak warga negara dan hak asasi manusia ternyata lebih tegas lagi diungkapkan dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang di dalamnya menyatakan bahwa Setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing (kursif penulis). Tentunya pengaturan mengenai HAM dalam bidang kepemilikan, terutama terhadap hak milik orang asing, telah dibatasi sedemikian rupa oleh negara. Sehingga berkaitan tentang hak kepemilikan tanah, pada dasarnya hanya dapat dimiliki kemudian oleh warga negara Indonesia, bukan oleh orang asing yang kedudukannya hanya tinggal untuk sementara waktu saja di Indonesia. Namun, jika seandainya orang asing tersebut, berkenginan untuk mempunyai hak milik atas tanah sebagaimana dimaksudkan di atas, maka untuk itu, telah ditentukan ada jalur yang selanjutnya dapat ditempuh oleh orang asing tersebut. Misalnya, dapat saja melalui perwarganegaraan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 Bab III tentang syarat dan tatacara memperoleh kewargenegaraan Indonesia atau yang kemudian lebih dikenal kembali dengan istilah naturalisasi (naturalization). Lebih lanjut pembedaan tentang HAM dan warga negara, di mana selanjutnya dimasukannya konsep warga negara ke dalam HAM (lihat Pasal 28D ayat (3) UUD 1945), hal mana pada dasarnya jelas-jelas memiliki arti berbeda, seperti apa yang dicontohkan di atas, termasuk juga dengan pengertian sebagaimana dimaksudkan, seperti yang telah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
586
dipaparkan tersebut di atas. Karena berkaitan antara kedudukannya, warga negara tentunya memiliki konsep yang benar-benar sangat berbeda dengan konsep hak asasi manusia. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ternyata diartikan merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijungjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan dilain pihak berkaitan dengan konsep warga negara menunjukan suatu kedudukan yang memang diperolehnya, dikarenakan orang tersebut merupakan warga dari negara tersebut. Dengan diberikannya status warga negara kepada seseorang, maka orang tersebut secara langsung memiliki hubungan dengan negara tersebut, bahkan hubungan tersebut adalah bersifat timbal balik, yang tentunya tidak mungkin akan dimiliki oleh orang asing, yang memang bukan sebagai warga negaranya. Dengan kata lain, bahwa orang asing dalam kenyataannya tidaklah memiliki hak dan kewajiban apapun dengan negara di mana tempat orang asing itu tinggal untuk sementara waktu saja. Karena memang hanya untuk warga negara saja yang ditentukan untuk memiliki hak dan kewajiban terhadap negara tersebut secara timbal balik. Terkait dengan konsepsi hak, maka menurut Soekanto (2008;20) adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan untuk kewajiban sendiri adalah suatu beban atau tugas. Tampaknya kemudian kekurang cermatan daripada anggota MPR di dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, khususnya antara ketentuan Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, berkaitan dengan konsep pengertian hak asasi manusia dan warga negara. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang pada dasarnya menyatakan bahwa calon Presiden dan/atau Wakil Presiden warga negara Indonesia sejak kelahirannya (Ius Sanguinis) dan tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, walaupun untuk selanjutnya menjadi warga negara Indonesia (naturalization). Sedangkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang pada dasarnya menyatakan Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (kursif penulis). Tentunya berkaitan dengan konsep hak asasi manusia adalah bersifat universal, sedangkan untuk hak warga negara adalah terbatas sifatnya, terutama dibatasi oleh ruang lingkup berlakunya hukum dari negara tersebut. Artinya adanya hak asasi manusia diakui keberadaannya, tanpa kemudian dibatasi oleh ruang dan waktu, di samping untu itu tanpa perlu diberikan oleh siapapun termasuk oleh negara sekalipun. Sedangkan, berkaitan dengan hak warga negara, yaitu merupakan suatu hak, yang pada hakekatnya mungkin hanya didapatkan oleh orang yang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
587
telah menganut suatu kewarganegaraan dari negara tertentu saja. Dengan demikian, tentunya terkait dengan perlakuan antara orang asing, apabila kemudian dibandingkan dengan warga negara akan berbeda-beda pula dalam suatu negara. Berhubung dengan adanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, yang di dalamnya dengan jelas menyatakan bahwa hanya sejak dilahirkan sebagai warga negara Indonesia, yang untuk selanjutnya dapatlah menjadi calon Presiden dan wakil Presiden. Tentunya, tidak mungkin dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden bagi seseorang yang sejak dilahirkan tidak berkewarganegaraan Indonesia. Atau dengan perkataan lainnya, bahwa dapatlah kemudian dikatakan orang tersebut pernah pula, memperoleh kewarganegaraan dari negara lain, walaupun mungkin untuk nantinya oleh Indonesia selanjutnya diberikan kewarganegaraan, baik dikarenakan adanya suatu permintaan (naturalisasi) oleh yang bersangkutan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia. Menurut hemat penulis, berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 adalah berkenaan dengan persyaratan untuk kemudian dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sejarahnya dahulunya, pernah terkait dengan jabatan Presiden ternyata dijabat oleh seorang yang dikabarkan pernah menerima kewarganegaraan lain, seperti B.J Habibie, yang santer dikabarkan mendapatkan kewarganegaraan Jerman. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, perlulah untuk di pahami terlebih dahulu bahwa dalam ketentuan Pasal 26 UUD 1945 tentang Warga Negara dan Penduduk, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, ditambah berkaitan dengan persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, yang kemudian perlu untuk ditambah lagi dengan UU tentang kewarganegaraan, yaitu UU No 12 Tahun 2006. Artinya dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sebenarnya tidak mungkin dapat diterapkan terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, walaupun dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 terdapat kata kesempatan dalam pemerintahan, hal mana dikarenakan sudah ditutup peluangnya oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, khususnya dengan adanya perkataan sejak lahir. Artinya, walaupun dalam kenyataan seseorang sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia, tentunya orang tersebut tidak mungkin dapat untuk dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, kalau kewarganegaraannya tersebut ternyata tidak didapatkannya sejak lahir. Yang sebenarnya berarti, jika seandainya orang yang berkeinginan untuk mencalonkan dirinya untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tentunya sudah berkewarganegaraan Indonesia (Ius Sanguinis) sejak lahir. Sehingga tidak mungkin dapat dicalonkan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, apabila dalam kenyataannya pernah memperoleh kewarganegaraan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
588
lainnya. Walaupun nantinya kewarganegaraan Indonesia dapat diperolehnya melalui jalur naturalisasi yaitu berupa permohonan kewarganegaraan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 12 Tahun 2006. Dengan demikian, adanya perkataan warga negara dalam konsep hak asasi manusia terutama oleh UUD 1945, dapatlah dikatakan merupakan suatu kekeliruan mendasar, apalagi kemudian berkehendak untuk menerapkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Karena dalam konsep pemerintahan, adalah bersifat nasional yang berarti sangat ditentukan oleh tempat dimana berlakunya peraturan tersebut, yang berarti bukanlah memiliki sifat universal. Dengan demikian, akan sepenuhnya bergantung daripada pengaturan yang nantinya akan dibuat oleh negara bersangkutan berkaitan dengan hak-hak dalam bidang pemerintahan. Selanjutnya, juga berkenaan dengan hak asasi manusia, khususnya di dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang dapat kemudian ditemui kata hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang memang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable). Kelemahan yang melekat dalam ketentuan tersebut adalah mutlaknya hak-hak yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, seperti hak untuk hidup, disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dikarenakan hak tersebut sudah ditentukan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, meskipun dalam kenyataannya kemudian dibatasi, terutama dengan adanya ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Yang kemudian menjadi pertanyaan mendasar yaitu apakah terhadap pelanggaraan hak asasi yang selanjutnya dikatagorikan berat seperti apa yang pernah terjadi masa lalu, di mana pemerintah ditengarai sebagai aktor utamanya, dapatkah kemudian diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Memang pada awal melakukan perubahan terhadap UUD 1945, ketentuan ini merupakan suatu polemik, yang banyak menyita waktu sejak dalam pembahasannya di MPR. Tidak lain, dikarenakan dapat kemudian dikatakan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dalam kenyataannya suatu tindakan yang seharusnya merupakan suatu perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun dikarenakan pada saat itu, belum adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran terhadap hak asasi, maka tidaklah dipandang sebagai perbuatan jahat. Maka seolah-olah terlihat bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak bersifat melanggar hukum, padahal sesungguhnyan jika kemudian dilihat dari sisi lain terutama dari sisi kemanusiaan, dapatlah dipandang merupakan suatu kejahatan, bahkan berat sifatnya. Namun, dikarenakan memang belum adanya hukum (law) yang sebelumnya mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dikatagorikan jahat, maka seakan-akan tindakan tersebut menjadi perbuatan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
589
yang dapat dipandang legal dimata hukum. Ketentuan ini mirip sekali dengan salah satu asas dalam hukum publik, yaitu hukum pidana (criminal law, strafrecht), yang kemudian biasanya disebut dengan nama asas legalitas atau lebih dikenal dengan bahasa Latinnya yang berbunyi : Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali, yang berarti tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Jika ditarik kesimpulan dari asas legalitas dalam hukum pidana tersebut di atas, maka kini dapat dikemukakan dua asas dalam hukum pidana tersebut, yaitu (1) bahwa sanksi pidana (strafsanctie) hanya dapat ditentukan dengan undang-undang (2) bahwa ketentuan sanksi pidana ini tidak boleh berlaku surut (geen terugwarkende kracht). Oleh karenanya, dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan, bahwa larangan berlaku surut terhadap segala tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, yang mungkin dulunya dilakukan. Sehingga, terhadap seorang yang disangka sebelumnya telah melakukan pelanggaran hukum berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut, tidak mungkin untuk dapat diadakan penuntutan berdasarkan ketentuan hukum yang baru sekarang diadakan, terutama ketentuan baru yang diadakan untuk mengatur mengenai pelanggaran hak terhadap asasi manusia. Walaupun sebenarnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang berbunyi apabila ada perubahan dalam perundang-undangan terjadi sesudah tindak pidana diperbuat, maka yang diperlakukan adalah ketentuan-ketentuan dari hukum lama atau hukum baru, yang lebih menguntungkan bagi si tersangka (Prodjodikoro,2008;44). Hanya saja, ketentuan tersebut tidak mungkin bisa untuk kemudian diterapkan di lapangan, dikarenakan seperti pernyataan tersebut di atas, bahwa pengaturan mengenai hak asasi manusia pada waktu itu memang belum ada landasan hukumnya sama sekali. Berarti peraturan pertama yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah Tap MPR No. XVII Tahun 1998, atau dengan kata lain, berkaitan dengan pengaturan hak asasi manusia baru diatur kemudian pada tahun 1998. Jadi sebelum peraturan tersebut keluar, maka pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidaklah mungkin untuk dapat dituntut di depan pengadilan. Bahkan, pada dasarnya Tap MPR sendiri bukanlah peraturan yang bersifat memaksa, karena di dalamnya belum terdapat sanksi yang tegas apabila normanya benar-benar dilanggar, karena memang masalah tersebut, perlulah diatur kembali lewat peraturan yang ada di bawahnya, seperti dalam bentuk undang-undang (sebelum diamandemennya UUD 1945). Jadi, jangankan adanya pertentangan ketentuan hukum, yaitu antara hukum baru dan hukum lama yang kemudian akan dikenakan terhadap tersangka sebagai pelaku terhadap pelanggaraan hak asasi manusia sebelum tahun 1998, bahkan dalam kenyatannya satu peraturan pun, tidaklah terdapat untuk menjamin berkaitan dengan pelangaran hak asasi manusia agar dapat diadili kemudian, hal mana tentunya dapat
I Gusti Ngurah Santika, SPd
590
dipandang sangat menguntungkan bagi tersangka. Menurut pendapat dari Abddullah dan Syamsir (2004;67) yang menyatakan bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tidak mengatur asas retroaktif, maka Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaraan hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan. Kekhawatiran penulis, terkait dengan permasalahan tersebut adalah adanya pihak-pihak yang kemudian mencoba untuk selanjutnya membebaskan dirinya dari suatu tindakan kejahatan, terutama terhadap pelanggaraan hak asasi manusia di masa lalu, dengan cara mencantumkan suatu ketentuan konstitusional, sehingga dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Adanya ketentuan ini menurut pendapat penulis, adalah sebagai upaya untuk melindungi orang-orang yang sebelumnya telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dengan mendasarkan dirinya pada upaya legalitas semata, yang kemudian dicantumkannya dengan jelas dalam UUD 1945. Namun, jika kita lihat kembali dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka ada suatu upaya lain untuk kemudian membatasi hak asasi manusia tersebut hanya dengan bentuk undangundang. Bunyi dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 , yaitu Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (kursif penulis). Dengan demikian, terlihat dalam UUD 1945 itu sendiri terdapat kontradiksi, antara pasal-pasal yang mengatur berkaitan dengan hak asasi manusia. Di satu pihak, ada ketentuan tentang hak-hak asasi yang memang telah ditentukan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, namun dilain pihak dipandang perlu, adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia tersebut. Tidak lain dikarenakan, pembatasan terhadap hak asasi manusia memang diperlukan, sehingga nantinya dapat memberikan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, di samping untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, untuk selanjutnya yang menjadi pertanyaan utama, yaitu apakah hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dapatkah kemudian dibatasi hanya dengan suatu UU, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945? Dengan pendapat yang sama, Budiardjo (2008;263) menyatakan bahwa sekalipun demikian,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
591
masalah retroaktif tetap merupakan suatu masalah konstitusional, yang menyangkut pertanyaan apakah hak yang dalam UUD 1945 dinyatakan sebagai hak asasi yang non derogable (bukan hak asasi biasa) dapat dibatasi oleh undang-undang, yang biasanya berada di tingkat bawah UUD. Sebenarnya pertanyaan ini telah terjawab, terutama pada saat pengujian undang-undang oleh MK terkait dengan legalitas daripada hukum mati. Yang mana menurut pemohon bahwa hukuman mati adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terutama hak manusia untuk hidup. Namun, akhirnya MK dengan 5;4 memutuskan, bahwa berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas daripada hukuman mati masih tetap berlaku (konstitusional) dikarenakan memang tidak bertentangan dengan konstitusi. Tidak lain, karena dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, telah diatur pula mengenai pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam bentuk undang-undang. Dapatlah kemudian dikemukakan contoh lain, misalnya kasus bom Bali yang tersangkanya untuk sekarang telah dihukum mati oleh negara. Bom Bali yang pada saat terjadinya peristiwa tersebut, merupakan suatu peristiwa yang memang belum terdapat suatu peraturan hukum tentang terorisme, terkait dengan adanya tindakan tersebut. Namun, setelah terjadinya peristiwa tersebut, kemudian belakangan hari menyusul berlakunya UU No 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Yang kemudian diuji kembali di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara No. 013/PUU-I/2003, yang pada akhirnya dibatalkan oleh MK, dikarenakan UU No. 16 Tahun 2003 bertentangan dengan semangat dari ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan ketentuan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Dalam kenyataan, dapatlah kemudian dikatakan bahwa dalam peristiwa tersebut memang belum ada peraturan, terutama pada saat tindakan tersebut dilakukan. Jika demikian, dapat pula dinyatakan bahwa pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28I UUD 1945 tersebut, tidaklah selanjutnya dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Namun, dalam masalah tersebut penulis berpedoman, bahwa setiap tindakan dalam suatu negara hukum, seharusnya dapat pula dipertangungjawabkan secara hukum, tentunya mencakup pula hukum yang tidak tertulis. Apalagi pada dasarnya tindakan tersebut benar-benar merugikan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia internasional. Maka, dalam hal tersebut pelaksanaan hak asasi manusia tentunya dibatasi pula oleh hak asasi manusia lainnya, sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan orang lain dalam suatu negara hukum yang demokratis. Bahkan untuk sekarang telah banyak pula keluar berbagai peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan dapat menjamin pelaksanaan hak asasi manusia di lapangan, seperti adanya UU No. 39 Tahun
I Gusti Ngurah Santika, SPd
592
1999, Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 serta Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. C. Amandemen Ketiga Terjadi Pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 9 November 2001. Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan Lembaga Negara Terjadi pula perubahan yang sangat mendasar terhadap UUD 1945, khususnya berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimana dari supremasi MPR yang sebelumnya ditentukan untuk melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kemudian terjadi perubahan secara drastis, yang selanjutnya berbunyi, yaitu menurut undang-undang dasar. Untuk itulah, dikatakan sekarang sistem ketatanegaraan yang telah anut tidaklah sama seperti sebelumnya, di mana dahulunya ditentukan ada sebuah lembaga negara yang memegang kekuasaan tertinggi bertugas untuk selanjutnya melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam Panduan Pemasyarakatan UUD NRI dan Ketetapan MPR RI (2011;64) yang di dalamnya menyatakan bahwa dengan perubahan itu tidak tidak dikenal istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Asshidiqie (2006;41) bahwa karena
I Gusti Ngurah Santika, SPd
593
kedudukannya yang tinggi, sekiranya lembaga-lembaga konstitusional ini hendak disebut sebagai lembaga tinggi negara juga dapat diterima. Dewasa ini, memang tidak dikenal lagi adanya lembaga tertinggi negara. Semua lembaga konstitusional dianggap sederajat dan hanya dibedakan dari perbedaan fungsi dan kewenangannya masing-masing (kursif penulis) Jika dicermati dari kalimat tadi, ternyata tidaklah dapat dikatakan sepenuhnya benar, karena hanya dengan menyatakan tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara. Bahkan, dapatlah diketahui kemudian, bahwa sebelum adanya Perubahan terhadap UUD 1945, memang dalam kenyataannya kita tidak pula mengenal sebutan lembaga tertinggi maupun tinggi negara. Hal mana hanya kemudian dapat ditemukan kembali dalam ketetapan MPR, yang ditentukan lebih lanjut untuk mengatur tentang hubungan antar lembaga-lembaga negara. Namun, untuk sekarang berkaitan dengan kedudukan lembaga negara, jika kemudian kita tinjau kembali dari segi wewenang, tugas dan fungsi yang diberikan oleh UUD 1945 atau jika dilihat dari sudut tersebut, maka dapatlah untuk selanjutnya dikatakan, bahwa MPR sebenarnya tetap merupakan lembaga negara yang kedudukannya paling tinggi. Paling tinggi kedudukan MPR sebagai lembaga negara, hanya mungkin dapat kita ketahui dari wewenang, tugas dan fungsinya yang kemudian diberikan oleh UUD 1945. Dikarenakan, bahwa MPR yang merupakan lembaga negara, dalam kenyataannya diberikan wewenang sangat besar oleh UUD 1945. Kewenangan besar sebagaimana dimaksudkan tersebut, yaitu untuk mengubah hukum dasar tertinggi, yaitu UUD 1945 (Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 37 UUD 1945), yang tentunya tidak dapat diberikan kepada lembaga negara lainnya. Dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki tersebut, MPR kemudian dapat melakukan apa saja, berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi, dapatlah kemudian dikatakan bahwa kedudukan MPR tetaplah lebih tinggi daripada lembaga negara lain, dikarenakan fungsi dan wewenangnya sangat luar biasa telah ditentukan dalam UUD 1945, yaitu untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa ada kekuasaan lembaga negara lainnya, yang dikemudian hari dapat mengimbanginya berkaitan dengan fungsi dan wewenangnya tersebut. Dengan argumen sama dapatlah selanjutnya ditemui kembali dalam pernyataan Soeprapto (2007;152), yang pada dasarnya menyatakan bahwa pendapat ini diajukan oleh karena sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan dan mengubah undang-undang dasar, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satunya lembaga yang lebih utama dari lembagalembaga negara lainnya. Dengan demikian, sebutan lembaga-tertinggi dan lembaga tinggi negara, bukanlah suatu yang harus dipermasalahkan, tetapi haruslah dipahami berdasarkan wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, oleh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
594
karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah juga tidak pernah menyatakan adanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Mekanisme Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden. Setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945, telah dibentuk pula sebuah lembaga negara yang bertugas untuk memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, serta berkaitan pula dengan pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Dengan adanya mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang jelas diatur di dalam UUD 1945, merupakan suatu perubahan yang dapat dikatakan sifatnya sangat mendasar, sehingga tentunya bisa dikatakan telah mempengaruhi sistem pemerintahan yang kemudian dianut oleh Indonesia. Sebelumnya UUD 1945 diamandemen adanya pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, di mana pada dasarnya MPR sendiri yang notabene merupakan sebuah lembaga politik, selain itu MPR juga ditentukan berwenang untuk membentuk peraturan hukum yang bersifat mengikat, seperti UUD 1945. Bahkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR tersebut, dengan alasan dikarenakan Presiden dan Wakil Presiden telah melanggar haluan negara yang sebelumnya dibentuk oleh MPR. Sedangkan, untuk haluan negara itu sendiri pengertiannya adalah sangatlah luas, dengan begitu, alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden lebih terlihat unsur politisnya. Dapatlah kemudian dicontohkan terutama pada saat pemberhentian Presiden pertama Indonesia Soekarno dan selanjutnya kembali terlihat lebih jelas unsur politisnya pada waktu pemberhentian Presiden Abdurahman Wahid sebagai Presiden keempat. Karena itu, sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh ketatanegaraan Indonesia, adalah sistem presidensial yang mengandung unsur parlementer atau quasi presidensial, terutama terkait dengan prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Namun, untuk sekarang ini, tampaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mungkin dapat diberhentikan dengan alasan-alasan tidak jelas, apalagi yang lebih bernuansa politis, seperti dalam sistem pemerintahan yang menganut parlementer. Karena pada dasarnya dalam UUD 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B, tentunya sudah cukup jelas dinyatakan berkaitan dengan alasan-alasan daripada pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Alasan-alasan hukum sebagaimana yang kemudian dimaksudkan dalam ketentuan UUD 1945, adalah berupa pengkhianatan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
595
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi, sebenarnya jika kita cermati kembali dengan saksama, ternyata ada suatu perbedaan yang cukup mendasar antata bentuk pertanggungjawaban Presiden dan wakil Presiden sebelum UUD 1945 diamandemen, dengan bentuk pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka akan terlihat tampak dengan jelas perbedaannya. Jika sebelum UUD 1945 diamandemen, terkait dengan adanya pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden adalah lebih berhubungan dengan masalah-masalah politis. Jadi pertanggungjawabannya adalah satu kesatuan daripada jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Karena jika dalam kenyataannya, MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, ternyata dikemudian hari menarik mandat Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka untuk itu, mau atau tidak mau Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih MPR sebelumnya tersebut, seharusnya berhenti dari jabatannya secara bersamaan. Sedangkan setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945, alasan-alasan yang kemudian digunakan dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945, untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidaklah lagi menggunakan alasanalasan yang bernuansa politis. Namun, untuk sekarang ini alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan menggunakan alasan-alasan hukum, yang kemudian perlu dibuktikan kembali dalam persidangan peradilan, yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi (previlegiatum). Jadi, adanya bentuk pertangungjawaban hukum, tentunya tidaklah dapat sama kemudian, dengan bentuk pertanggungjawaban politik. Secara hukum, pertanggungjawaban dianut dalam sistem hukum kita adalah perorangan (individual), sehingga di dalamnya terdapat kata dan/atau yang menunjukan bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama melakukan perbuatan yang benar-benar bersifat melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945, maka keduanya dapat diberhentikan bersamaan. Namun, jika hanya Presiden atau Wakil Presiden saja yang melakukan tindakan bertentangan dengan larangan-larangan yang ditentukan dalam UUD 1945, maka dengan demikian yang selanjutnya akan bertanggungjawab adalah Presiden atau Wakil Presiden. Sehingga bentuk pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden secara hukum, bukan secara bersamaan sebagaimana dalam bentuk pertanggungjawaban politis, kecuali bilamana memang dalam kenyataannya Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ada di dalam UUD 1945 secara bersamaan. Namun, yang selanjutnya menjadi permasalahan berkaitan dengan impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden, adalah berkaitan dengan prosesnya dalam sistem
I Gusti Ngurah Santika, SPd
596
ketatanegaraan Indonesia yang telah ditentukan di dalam UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, ternyata di dalamnya juga melibatkan tiga lembaga negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diawali dengan adanya pendapat dari DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, atau DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian dengan adanya dukungan daripada 2/3 anggota DPR, maka dapatlah kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya diputuskan, apakah benar bahwa Presiden dan/atau Wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum menurut pendapat DPR tersebut. Ataupun selanjutnya MK memutuskan dengan membenarkan pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian apabila sudah terbukti (sesuai dengan putusan dari MK), maka berkenaan dengan adanya putusan MK tersebut, selanjutnya DPR mengadakan sidang dengan tujuan untuk melanjutkan kembali dakwaannya ke MPR, guna meminta keputusan yang bersifat final dan mengikat dari MPR, apakah nantinya akan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau tidak. Sebelum MPR mengambil keputusan untuk kemudian memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, telah ditentukan pula bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sebelumnya telah diputuskan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam kenyataannya Presiden dan/atau Wakil Presiden kembali diberikan suatu kesempatan untuk selanjutnya menyampaikan penjelasannya dalam rapat paripurna MPR. Setelah itu, maka barulah kemudian MPR mengambil keputusan, apakah nantinya benar-benar akan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau tidak. Bagaimana jawaban tersebut dapat diketahui, tentunya akan sangat tergantung pula daripada kuorum yang nantinya dapat tercapai, seperti yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, yaitu harus dihadiri dalam rapat paripurna sebanyak 3/4 dari jumlah anggota MPR, kemudian disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Namun, apabila dikemudian hari Mahkamah Konstitusi memutuskan, bahwa dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa dakwaan dalam bentuk pendapat DPR tersebut dalam kenyataannya tidak terbukti, maka DPR tidak mungkin dapat kembali untuk melanjutkan permintaan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, untuk selanjutnya mengambil keputusan final apakah akan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau tidak.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
597
Terkait dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang dimaksud tersebut di atas, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah letak permasalahan yang kemudian dihadapi, khususnya dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca perubahan? Letak permasalahan berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, sebagaimana yang kemudian dapat penulis temui dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, adalah mengenai letak kewenangan terakhir/final untuk kemudian memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di antara dua lembaga negara, yaitu antara MPR dan Mahkamah Konstitusi. Dalam kenyataannya, jika selanjutnya kita berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (3), 7A dan 7B UUD 1945, maka akan tampak jelas terlihat bahwa yang sebenarnya berhak dan memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah MPR. Sedangkan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR, maka perlulah terlebih dahulu mendapatkan keputusan hukum, khususnya dari lembaga peradilan agar nantinya dapat menjamin secara hukum, bahwa dugaan oleh DPR tersebut, memang benar-benar dapat dibuktikan secara hukum, lewat forum previlegiatum terutama dengan adanya keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Namun, kenapa dalam mengambil keputusan untuk kemudian memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945 ataupun sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, dalam kenyataannya kembali menggunakan syarat-syarat politis, seperti kourum yang selanjutnya dipersyaratkan kembali dalam ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945? Bahkan, mengapa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sebelumnya sudah tegas-tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bersalah, karena terbukti melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, dalam kenyataannya masih diberikan suatu kesempatan kepadanya untuk kemudian menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR? Berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan tersebut di atas, apakah dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar sudah sesuai dengan konsep negara, yang meletakan posisi hukum pada kedudukan tertinggi (superior, supreme)? Penulis rasa, pangkal permasalahan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebenarnya terletak pada keputusan MK, yang ditentukan tidaklah memiliki kekuatan mengikat dan final untuk dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, jika memang terbukti melanggar hukum ataupun larangan lainnya sesuai dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
598
ketentuan Pasal 7A UUD 1945. Atau dengan kata lain, bahwa kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah membuktikan, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam kenyataannya telah melakukan suatu tindakan yang bersifat melanggar hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 ataupun telah terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, ternyata sangatlah tergantung pada dukungan suara daripada MPR. Bahkan, dalam kenyataannya suara yang kemudian diambil oleh MPR sendiri untuk selanjutnya memutuskan, apakah benar-benar akan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ataupun tidak, ternyata baru diambil kemudian, setelah adanya penjelasan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apakah dengan demikian terkait dengan penjelasan yang diberikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, apabila kemudian dibandingkan dengan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi, memiliki nilai/kekuatan sama di depan rapat paripurna MPR? Tampak pernyataan tersebut memang benar, bahwa terkait dengan penjelasan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang sebelumnya telah ditetapkan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kemudian pada saat rapat paripurna MPR, seakan-akan memiliki nilai yang sama dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. karena terkait dengan kemungkinan diantara kedua hal tersebut (penjelasan Presiden atau putusan MK) yang akhirnya akan dijadikan dasar bagi pertimbangan MPR dalam mengambil keputusannya kelak, hal mana tentu nantinya akan tampak terlihat jelas dari kuorum yang dicapai. Seandainya saja, dalam kenyataannya penjelasan yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada saat sidang paripurna MPR, ternyata berhasil menyentuh hati anggota-anggota MPR, maka dapatlah dipastikan kuorum yang kemudian diharapkan, tidak akan terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, untuk dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun, apabila dalam kenyataannya MPR, tidak menerima penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka putusan Mahkamah Konstitusi lah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman MPR, dalam rangka pengambilan keputusan, untuk kemudian memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang tentunya harus sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945. Dalam pada itu, yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya, yaitu apakah sesuai prosedurnya apabila selanjutnya Presiden dan/Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna? Penjelasan apakah yang hendak disampaikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang sebelumnya telah terbukti bersalah melanggar larangan-larangan dalam UUD 1945, sesuai dengan pendapat DPR yang telah memperoleh kekuatan hukum, lewat putusan hukum Mahkamah Konstitusi? Mengapa penjelasan Presiden dan/atau Wakil
I Gusti Ngurah Santika, SPd
599
Presiden tidak lebih baik disampaikan saja ketika berlangsungnya proses peradilan ketatanegaraan di Mahkamah Konstitusi, hal mana peradilan tersebut bertugas untuk memutuskan pendapat DPR, berupa dugaan mengenai pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ataupun kemudian terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945? Sebenarnya tampak terlihat dengan jelas, bahwa adanya pengaturan berupa ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, berkaitan dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, yang pada dasarnya meletakan prinsip utama bahwa setiap orang kedudukannya sama di hadapan hukum (equality before of the law), walaupun kemudian yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut, adalah seorang yang kebetulan menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi, Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sebenarnya sudah jelas-jelas terbukti bersalah menurut pendapat DPR, yang sebelumnya telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan (forum previlegiatum), dalam kenyatannya masih diberikan kesempatan untuk selanjutnya menyampaikan penjelasan kepada MPR dalam rapat paripurna, sebelum pada akhirnya MPR mengambil keputusannya apakah benar-benar akan memberhentikan atau tidak, terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang didakwa oleh DPR. Namun, jika kemudian kita lihat kembali terkait dengan sistematika daripada mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik yang selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A dan 7B dan juga dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka kemudian tampak terlihat bahwa skenario politik yang dibangun oleh MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, khususnya berkaitan dengan proses impeachment (pemberhentian) Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidaklah terdapat aturan yang tumpang tindih antara satu sama lainnya. Sebab jika diperhatikan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945. Oleh karena itu, kita harus menyelidiki kembali dalam UUD 1945, terutama ketentuan lainnya dari UUD 1945, terutama berkaitan dengan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, diharapkan selanjutnya kita dapat lebih mengetahui dan memahami bagaimana sebenarnya prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pertama kita cermati dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 di sana telah ditentukan dengan jelas mengenai lembaga-lembaga negara mana saja yang ikut terlibat langsung, kemudian kewenangannya di samping alasan-alasan yang bisa digunakan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk pula berkaitan dengan tata cara pemberhentian Presiden
I Gusti Ngurah Santika, SPd
600
dan/atau Wakil Presiden. Lebih lanjut, jika kita lihat kembali dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi (constitutional court) berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusan bersifat final berkaitan dengan kewenangan tertentu. Sedangkan dalam ketentuan ayat (2) dari Pasal 24C UUD 1945, yang di dalamnya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR, mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Kesimpulan yang kemudian penulis peroleh, berkaitan dengan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, adalah kita tidak mungkin hanya dapat mengambil keputusan terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, jika kemudian kita hanya melihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. Sehingga, berkaitan dengan masalah tersebut, kita harus kembali melirik/menengok dalam ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Karena dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diserahkan kembali pengaturannya menurut UUD 1945. Nasib yang tentunya sama, ternyata juga dialami oleh ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, bahwa putusan MK atas pendapat DPR, terkait dengan dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dalam kenyataan selanjutnya diserahkan kembali pengaturannya menurut UUD 1945. Dengan demikian, hanya dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang sesungguhnya menurut undang-undang dasar di dalamnya terdapat proses pemberhentian presiden dan/atau Wakil Presiden. Dari sinilah kemudian permasalahan ketatanegaraan mulai timbul, yaitu jika seandainya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), yang pada dasarnya meletakan kedudukan hukum lebih tinggi apabila dibandingkan dengan politik. Hal mana berkaitan dengan masalah tersebut, dalam kenyataannya Mahkamah Konstitusi tidaklah berwenang untuk memutuskan kata akhir (final) berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam UUD 1945. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebenarnya adalah kewenangan MPR, bukan pada Mahkamah Konstitusi, namun dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden perlulah untuk terlebih dahulu mendapatkan keputusan dari MK. Dengan demikian, pada dasarnya MK hanya dapat memutuskan pendapat DPR bukannya mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung, karena dengan adanya ketentuan inilah, yang pada akhirnya menyebabkan MK, tidak dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung. Walaupun Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, lewat pendapat DPR
I Gusti Ngurah Santika, SPd
601
sebelumnya. Meskipun dengan adanya pengaturan seperti ini, nantinya akan berdampak positif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ke depannya, dimana dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, khususnya jika kemudian dikaitkan dengan hukum pidana, yaitu dalam kenyataannya tidaklah melanggar asas ne bis in idem dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang berbunyi kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (heziening), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap (Moeljatno,2005;32). Asas ne bis in idem, yaitu apabila putusan pengadilan tersebut merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah memperoleh kekuatan tetap (Kuffal,2004;230). Dengan demikian, Presiden dan/atau Wakil Presiden masih dapat diadili pada peradilan umum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana dikarenakan bukan orangnya yang putus oleh MK, melainkan hanya pendapat DPR. Jadi tentunya prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidaklah melanggar prinsip ne bis in idem dalam hukum pidana Yang menjadi masalah kemudian adalah mengenai keputusan MK tersebut, yang dalam kenyataannya bukanlah keputusan bersifat final dan mengikat. Hal tersebut, dikarenakan bahwa setelah adanya keputusan dari MK, ternyata ditentukan kemudian, bahwa DPR akan melanjutkan untuk kembali meneruskan dalam rapat paripurna MPR. Yang kemudian putusan dari MK tersebut, kembali diusulkan oleh DPR kepada MPR, untuk selanjutnya diputuskan secara politis, apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak. Tentu diberhentikan atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden, akan tercermin kemudian dari hasil pemungutan suara di MPR. Namun, ditentukan bahwa sebelum MPR mengambil keputusan, ternyata juga memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu di depan rapat paripurna MPR. Adanya penjelasan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam rapat paripurna MPR, tentunya bisa saja untuk dimungkinkan, dikarenakan sebelumnya terutama dalam proses persidangan yang berlangsung di MK, Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam kenyataannya tidak memberikan penjelasan atau pembelaan diri, terutama terhadap dakwaan yang diajukan DPR, terkait dugaannya bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum dan pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Dengan demikian, apakah dapat selanjutnya diterima argumen yang menyatakan seperti itu? Tentu, rasanya lebih tepat jika seandainya memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, untuk membela dirinya di dalam proses persidangan di MK. Pendapat demikian disampaikan, tidak lain di MK sebagai suatu lembaga peradilan, merupakan tempat berlangsungnya pembuktian bagi
I Gusti Ngurah Santika, SPd
602
pendapat DPR, tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Dengan demikian, tidaklah mungkin untuk menyatakan seseorang telah bersalah, karena melakukan pelanggaran hukum, tanpa sebelumnya mendengar pihak lainnya, khususnya terdakwa untuk selanjutnya di dengar pendapat tersebut, berupa suatu pembelaan terhadap dirinya. Bahkan, dalam hukum acara sendiri, di dalamnya terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa kedua belah pihak harus didengar (DPR dan Presiden), yang kemudian lebih dikenal dengan istilah yaitu, audi et alteram partem atau Eine Mannes Rede ist Mannes Rede, man soll sie horen alle beide. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya (Mertokusumo,2006;15). Tentunya, setelah diberikannya kesempatan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, untuk menjelaskan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, bahwa sebenarnya dirinya tidaklah bersalah. Apakah setelah itu masih perlukah Presiden dan/atau Wakil Presiden memberikan kembali penjelasan di dalam rapat paripurna MPR? Apakah dengan demikian, tidak bertentangan dengan konsep negara hukum, yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum? Yang berarti tidak melihat, entah seseorang tersebut berkedudukan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang jelas dalam proses berperkara di peradilan harus dinyatakan sama kedudukannya, tanpa ada suatu bentuk pengistimewaan apapun. Bahkan, yang menjadi kesulitan di sini, adalah berkaitan dengan penjelasan apakah yang kemudian hendak disampaikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam rapat paripurna MPR? Dikarenakan penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelumnya, seperti yang sudah disampaikan dalam persidangan MK, terkait tentang pembelaan dirinya, dalam kenyataannya tidak dapat diterima, terutama lewat putusan MK, yang selanjutnya menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaraan hukum atau pelanggaran lainnya, sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama berkaitan dengan prosedur peradilannya sangatlah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mertokusumo (2011;130), dengan menyatakan, yaitu pada hakekatnya, forum previlegiatum itu merupakan semacam limited jurisdiction (peradilan khusus/istimewa) bagi orang-orang tertentu, yang ditarik dari peradilan umum dan berfungsi melindungi kepentingan. Dari kesimpulan yang kemudian diperoleh dari paparan tersebut di atas, adalah mengenai putusan MK bukanlah putusan yang bersifat final dan mengikat, dikarenakan kemudian dapat dianulir kembali oleh MPR. Bahkan, dengan pemberian kesempatan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk selanjutnya memberikan penjelasan kembali dalam rapat paripurna, pada dasarnya telah memberikan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
603
cacad tersendiri terhadap dunia peradilan di Indonesia. Dikarenakan sebelumnya Presiden dan/atau Wakil Presiden telah dinyatakan bersalah dalam persidangan di MK, terutama lewat putusan MK terhadap pendapat DPR terkait dengan pelanggaran menurut UUD 1945. Dengan demikian, dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, secara tidak langsung telah membuktikan prosedur hukum kita terutama dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebenarnya tidaklah mungkin dapat dikatakan meletakan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum. Namun, perlu diingat kemudian bahwa tanpa ada keputusan dari MK yang memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah secara hukum, yaitu dengan membenarkan pendapat DPR sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Maka dapatlah dipastikan kemudian bahwa MPR tidak mungkin dapat melaksanakan kewenangannya, terutama untuk selanjutnya memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena dengan adanya putusan dari MK yang menyatakan pendapat DPR, khususnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ataupun larangan lainnya menurut UUD 1945 ternyata tidak terbukti. Maka tentu, untuk selanjutnya DPR tidak dapat melanjutkan kembali untuk mengadakan sidang paripurna, untuk dapat selanjutnya mengajukan permintaan kepada MPR guna memutuskan, apakah nantinya benar-benar akan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berarti keputusan MK tersebut, sebenarnya tetaplah bersifat finaldan mengikat, hanya saja jika dikemudian hari Presiden dan/atau Wakil Presiden diputuskan tidak melanggar hukum ataupun larangan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Dengan demikian, kesimpulan yang kemudian penulis peroleh, khususnya dari proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu dalam kenyataannya UUD 1945, telah memberikan perlindungan yang ekstra kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. Alasan penulis menyatakan demikian, yaitu Pertama, bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar akan terhenti, jika saja ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya menyatakan dugaan pelanggaran hukum dan pelanggara lainnya, yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, sebagaimana dimaksudkan oleh pendapat DPR ternyata tidak terbukti. Kedua, dengan adanya putusan MK yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah menurut UUD 1945 lewat putusannya, dalam kenyataannya tidak dapat langsung begitu saja memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya, karena diperlukan dukungan suara untuk menguatkan kembali putusan MK, dukungan suara sebagaimana dimaksudkan adalah berasal dari MPR. Jadi, pada dasarnya kewenangan terakhir pemberhentian Presiden
I Gusti Ngurah Santika, SPd
604
dan/Wakil Presiden adalah tetap berada di tangan MPR untuk memutuskan, walaupun setelah adanya keputusan dari MK yang menyatakan dengan membenarkan pendapat DPR, tentang Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945. Masalahnya kemudian, bahwa MPR merupakan sebuah lembaga politik, sedangkan MK adalah lembaga peradilan, di mana tentunya pertimbangan keputusan yang akan diambil pastinya berbeda pula di antara kedua lembaga negara tersebut. Tentunya antara pertimbangan politik yang selanjutnya diambil oleh MPR, hal mana tampak jelas dengan kekuatan suara yang mendukung atau tidak, terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan, pertimbangan hukum yang kemudian diambil oleh Mahkamah Konstitusi, yang terlihat jelas dengan dasar-dasar pertimbangan dalam putusannya, yang tentunya juga didasari oleh bukti-bukti kuat. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh MPR berdasarkan ketentuan Pasal 7B UUD 1945, dengan suara mayoritas dalam mengambil suatu putusan, apakah selanjutnya akan mendukung keputusan MK atau menentukan lain daripada keputusan MK, yaitu dengan membebaskan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan penjelasannya seperti apa yang disampaikannya pada saat rapat paripurna. Masalah besar akan timbul nantinya, apabila dikemudian hari putusan yang diambil oleh MPR, dalam kenyataannya berbeda pula dengan keputusan dari MK. Misalkan saja, jika MK selanjutnya memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tuduhan seperti dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, namun bisa saja kemudian karena dukungan politik yang diperolehnya di MPR, ternyata memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diberhentikan. Karena mungkin saja jumlah suara di MPR dipersyaratkan, ternyata tidak dapat memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, untuk selanjutnya memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam pada itu, tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang pada dasarnya menganut supremasi hukum (supremacy of law) bukannya supremasi politik. Namun, apabila dalam kenyataannya Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar tidak diberhentikan oleh MPR, terutama setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, yang tentunya berarti politik determinan terhadap hukum. Inilah konsep yang dapat dikatakan keliru terhadap mekanisme check and balances yang sebenarnya dikehendaki untuk kemudian diterapkan dalam UUD 1945, terkait dengan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga peradilan, yang memiliki kekuasaan merdeka dalam memutuskan suatu perkara dibidang ketatanegaraan. Apakah dengan demikian, lembaga politik seperti MPR, dapat kemudian melakukan pengawasan untuk mengimbangi lembaga peradilan, yaitu MK,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
605
dengan menganulir putusan dari MK, yang pada dasarnya telah menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah, lewat putusannya terhadap dugaan DPR dalam bentuk pendapat tersebut? Tentunya campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, merupakan pelanggaran nyata terhadap asas negara hukum, apalagi dilakukan kemudian oleh lembaga yang berada di luar kekuasaan kehakiman, karena MK sendiri sebenarnya merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Walaupun jelas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan putusan MK, berkaitan dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah merupakan suatu kewajiban hukum, bukannya suatu hak ataupun kewenangan, sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dapat kemudian ditafsirkan bahwa putusan MK tidaklah bersifat final dan mengikat, seperti putusan-putusan lainnya dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Menurut penulis, letak permasalahannya adalah cacad bawaan, yaitu prosesnya yang memang tidak benar dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, sehingga untuk ke dapan apabila ada suatu kesempatan untuk melakukan perubahan kembali terhadap UUD 1945, perlu untuk dipikirkan lagi dengan membuat proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang benar-benar sesuai dengan konsep negara, agar dapat dikatakan menganut prinsip-prinsip negara hukum demokratis (democratische rechtstaat). Selain itu, jika dalam kenyataannya Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar diberhentikan oleh MPR, ternyata permasalahannya tidak berhenti sampai di situ saja. Karena setelah diberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya oleh MPR, ternyata tidak menutup peluang dikemudian hari untuk dilanjutkan kembali penuntutan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diberhentikan oleh MPR pada peradilan umum. Hal mana tentunya akan berbeda jika putusan MK, hanya mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terkait dengan alasan, dikarenakan Presiden dan/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, di samping dalam UU pelaksanaannya yaitu UU No. 23 Tahun 2003 dan UU No.42 Tahun 2008. Yang mana juga sangat sesuai dengan penjelasan sebagaimana dimaksudkan sebelumnya di atas, bahwa prinsip pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidaklah melanggar prinsip ne bis in idem. Alasan untuk melanjutkan proses penuntutan terhadap mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden di depan peradilan pidana. Dikarenakan mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar telah melakukan pelanggaraan hukum, dalam bentuk pengkhianatan terhadap negara (UU No 27 Tahun 1999), korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, tindak
I Gusti Ngurah Santika, SPd
606
pidana berat lainnya, yaitu diancam dengan penjara lima tahun lebih menurut UU No. 24 Tahun 2003 (dalam Pasal 10 ayat (3)). Semua tindakan pelanggaran hukum ini, merupakan kewenangan (kompetensi) peradilan umum, untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sebelumnya sudah diberhentikan oleh MPR. Namun, tidak menutup kemungkinan keputusan peradilan umum mungkin saja akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga untuk itu dapat saja, menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum (rechtzekerheid). Tentunya, terkait dengan masalah tersebut penulis berpendapat bahwa keputusan yang kemudian diambil oleh peradilan umum, sudah pastinya diharapkan sesuai dengan keputusan dari MK, agar dapat lebih menjamin kepastian hukum. Dalam pada itu, akan terjadi masalah ketatanegaraan yang luar biasa, jika ternyata dikemudian hari, keputusan yang kemudian diambil oleh peradilan umum berlawan secara diametral dengan putusan MK. Hanya saja, jika diharuskan peradilan umum untuk menyesuaikan dengan keputusan daripada MK, maka dapat saja ditafsirkan bahwa kita secara tidak langsung telah melanggar prinsip kemerdekaan hakim dalam memutus perkara, termasuk dalam mengadili mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam bidang pidana. Untuk itu, perlu dipikirkan kembali berkaitan dengan permasalahan ini, yang mungkin saja dapat timbul dikemudian hari. Namun, tentunya semua alat bukti yang telah sebelumnya telah disampaikan oleh DPR di depan persidangan MK, pastinya dapat pula disampaikan kembali pada peradilan umum, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dikemudian hari, oleh hakim. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (constitutional review and judicial review). Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya kekuasaan dalam bidang hak uji materiil/formal peraturan perundang-undangan (yudicial review, or toetsingrecht), yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menurut UUD 1945, mungkin saja menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Dikarenakan adanya kompetensi silang dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh kedua lembaga negara tersebut. Dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dapatlah dilihat kemudian bahwa ditentukan adanya silang kompetensi antara tugas Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, dalam masalah pengujian peraturan perundang-undangan (yudicial rivew or toetsingrecht). Di mana ditentukan dengan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi (constitutional court) berwenang untuk menguji
I Gusti Ngurah Santika, SPd
607
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (constitutional review). Sedangkan dilain pihak, Mahkamah Agung (supreme court) ditentukan memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (yudicial review). Dengan kata lain, bahwa batu uji yang dipakai oleh MK adalah UUD 1945, yang tentunya berlainan sekali dengan MA, yang menggunakan UU sebagai batu uji sedangkan yang diuji adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UU. Masalahnya adalah jika dikemudian hari dalam kenyataannya, terjadi suatu pengujian peraturan perundang-undangan pada waktu bersamaan di antara kedua lembaga negara tersebut, terutama dengan produk hukum yang tentunya juga sama terkait materinya, khususnya jika ditinjau secara vertikal. Misalnya, di mana Mahkamah Agung menguji suatu Peraturan Pemerintah terhadap undang-undang. Sedangkan dilain pihak, pada waktu bersamaan, ternyata undang-undang yang dijadikan patokan atau batu uji oleh MA dalam melakukan pengujian terhadap peraturan pemerintah tersebut, sedang diuji konstitusionalitasnya di MK, dalam bentuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (constitutional review). Bisa saja, kemudian Mahkamah Agung dalam putusannya, menyatakan Peraturan Pemerintah tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang yang dijadikan batu ujinya. Sedangkan dipihak lain, terutama dalam waktu yang bersamaan ternyata undang-undang yang dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung, tiba-tiba juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Tumpang tindih terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu permasalahan mendasar, yang tidak menutup kemungkinan akan timbul dikemudian hari. Dikarenakan dengan adanya kompetensi silang dalam bentuk kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan teori dari stufentheori dari Han Kelsen, yang pada dasarnya menyatakan norma hukum suatu negara berjenjang dan bertingkat, yang membentuk tertib hukum. Norma yang di bawah berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang kedudukannya lebih tinggi, norma yang kedudukannya lebih tinggi berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang kedudukannya lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya. Maka dapatlah kemudian dikatakan bahwa berkaitan dengan kompetensi silang dalam pengujian peraturan perundang-undangan, misalnya pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MK, sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang yang dilakukan oleh MA, tentunya akan mengalami permasalahan yang cukup serius. Undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, dari peraturan yang berada di bawahnya, bisa saja dalam kenyataannya dihapuskan oleh
I Gusti Ngurah Santika, SPd
608
MK, dikarenakan sesuai dengan kewenangannya. Maka secara otomatis, semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang sebenarnya merupakan delegasi undang-undang tersebut, secara teori seharusnya juga ikut terhapus. Hal mana dikarenakan peraturan yang ada di bawahnya, seharusnya memiliki dasar dan bersumber pada peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Pendapat tersebut dinyatakan, karena sumber dari norma yang ada di atasnya tersebut, telah hapus oleh adanya putusan MK, atau dengan kata lain, tempat norma yang berada di bawah tersebut untuk bergantung terhadap norma yang ada di atasnya telah dihapuskan oleh MK. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa norma yang ada dibawahnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dikarenakan norma yang mendasar kelahiran peraturan tersebut sudah terhapus oleh putusan MK. Terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan antara MK dan MA, Mahmud MD (2010;134) memberikan catatan terutama mengenai kompetensi silang pengujian meteriil dari dua lembaga kehakiman (MA dan MK) itu, yaitu sebagai berikut. 1. Idealnya, MK menangani konflik peraturan perundang-undangan guna menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan. Lembaga ini sebaiknya hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seharusnya diberikan pada MK. 2. Idealnya, MA menangani konflik antar orang dan/atau badan hukum dan/atau lembaga termasuk konflik tentang hasil pemilu, konflik antara lembaga negara, perkara pembubaran parpol, dan pernyataan DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden baik karena pelanggaran atas hal-hal tertentu yang ditentukan di dalam UUD maupun karena terjadinya sesuatu yang menyebabkannya tidak lagi memenuhi syarat. Bahkan, berkenaan dengan adanya kompetensi silang tentang kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara MK dan MA, maka untuk sekarang setahu penulis, terdapat ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada ketentuan Pasal 55 telah memberikan solusi untuk mencegah masalah ini agar jangan sampai timbul dikemudian hari. Di mana ketentuan tersebut pada intinya menyatakan, jika seandainya MK sedang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (constitutional review), sedangkan pada waktu bersamaan MA ternyata juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan undang-undang sebagaimana dimaksudkan di atas merupakan batu uji yang digunakan oleh MA untuk menguji peraturan yang berada di bawah undang-undang
I Gusti Ngurah Santika, SPd
609
tersebut, namun dalam waktu bersamaan undang-undang tersebut sedang diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 oleh MK. Maka untuk itu, MA wajib untuk selanjutnya menghentikan sementara waktu, berkaitan dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tersebut, sampai kemudian adanya keputusan final dan mengikat dari MK terkait dengan konstitusionalitas undang-undang tersebut. Seharusnya berkaitan dengan kewenangan pengujian peraturan perundangundangan, hanyalah diberikan kepada satu lembaga negara saja. Dasar pemikiran ini, tidak lain dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan mulai dari atas sampai dengan yang kedudukannya paling rendah, di mana tentunya hanya dapat dilakukan oleh satu lembaga negara. Misalnya dapat saja suatu peraturan pemerintah yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan undang-undang, ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut. Namun, dapat saja dalam kenyataannya peraturan pemerintah tersebut, benar-benar bertentangan dengan UUD 1945. Tentunya, berkaitan dengan masalah tersebut, maka MA tidak mungkin dapat untuk membatalkan peraturan pemerintah tersebut, dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945. Hal mana karenakan kita mengetahui bahwa batu uji daripada pengujian yang dilakukan oleh MA berdasarkan pada undang-undang. Jadi, untuk meletakan prinsip negara yang mendasarkan diri pada supremasi hukum, maka semua itu tercermin dalam supremasi konstitusi. Sehingga seharusnya semua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan hukum tertinggi. Sehingga jangan sampai dikemudian hari ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan konstitusi, namun dalam kenyataannya tidak bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, yang mendasari kelahirannya. Inilah dasar pemikiran yang selanjutnya memiliki tujuan, untuk memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, dari mulai yang kedudukannya paling tinggi sampai dengan kedudukannya paling rendah, hanya kepada satu lembaga negara saja. Lebih lanjut berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang kemudian menjadi pertanyaan, yaitu apakah kewenangan yang dimiliki oleh MK, yang untuk selanjutnya ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, apakah sifatnya terbatas ataukah tidak terbatas terkait dengan materi apa saja yang dapat diujikan? Karena masih ada keraguan penulis, apakah MK yang ditentukan berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, khususnya undangundang tersebut merupakan hasil ratifikasi daripada suatu perjanjian internasional. Karena pada dasarnya, undang-undang tersebut merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional, yang telah dibuat dan disepakati antar negara, yang semuanya berkaitan dengan perjanjian
I Gusti Ngurah Santika, SPd
610
tersebut sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam hukum internasional. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst (Belanda) atau contract (Inggris). Sedangkan untuk kata internasional berarti telah melintasi batas negara, atau menyangkut lebih daripada satu negara yang ikut terlibat. Dengan demikian, pembuatan perjanjian internasional tentunya selalu melibatkan lebih daripada satu pemerintah negara saja. Bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula, maka perlu untuk diratifikasi. Dalam pada itu, prosedur yang dipakai di setiap negara mengenai ratifikasi adalah berbeda-beda (Starke,2008;602). Untuk kasus Indonesia, suatu perjanjian internasional hanya dapat berlaku dan mengikat rakyat Indonesia sebelumnya harus diratifikasi terlebih dahulu oleh DPR sebagai wakil rakyat sesuai dengan tahapantahapannya. Sehingga adanya ketentuan tersebut merupakan syarat utama, untuk berlaku atau mengikatnya perjanjian internasional terhadap negara-negara yang ikut terlibat untuk mengadakan perjanjian tersebut sehingga pada akhirnya mengikat rakyat negara tersebut. Menurut Rudy (2009;127-128) terkait dengan adanya tahapan-tahapan dalam membuat perjanjian internasional adalah perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan ratifikasi (ratification). Sedangkan dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2000, terkait dengan tahapan-tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional dimulai dari penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Telah ditentukan pula, tentang materi apa saja dalam perjanjian internasional yang kemudian harus diatur kembali dengan bentuk undang-undang. Hal tersebut terutama berkaitan dengan suatu perjanjian internasional lainnya, yang menimbulkan akibat luas dan mendasar, apalagi memiliki keterkaitan dengan beban keuangan negara yang nantinya akan membebani rakyat, haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR (Pasal 11). Dengan demikian, persetujuan yang diberikan oleh DPR terkait dengan perjanjian internasional tentunya dalam bentuk undang-undang. Dalam ketentuan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000, telah ditentukan pula, materi perjanjian internasional apa saja yang perlu diratifikasi agar selanjutnya dapat menjadi undangundang, yaitu masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak
I Gusti Ngurah Santika, SPd
611
berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri (kursif penulis). Pertanyaan yang selanjutnya penulis ajukan terkait dengan masalah tersebut di atas, yaitu apakah Mahkamah Konsititusi dapat menguji produk hukum internasional, yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari DPR, dengan bentuk hukumnya undangundang dan bagaimana pula implikasinya dalam hukum internasional? Selain masalah tersebut, yang selanjutnya menjadi pertanyaan lainnya, yaitu apakah suatu perjanjian internasional yang sebelumnya dibuat antar negara-negara, padahal negara itu sendiri merupakan salah satu subjek daripada hukum internasional (international law), kemudian dalam kenyataannya dibatalkan oleh MK, yang hanya merupakan organ dari suatu negara yang mengadakan perjanjian internasional tersebut? Penulis menyatakan negara sebagai salah satu subjek dari hukum internasional, dikarenakan ternyata masih ada subjek dalam hukum internasional lainnya, seperti Tahta Suci, Palang Merah Internasional (PMI), Organisasi Internasional, Perorangan (Individu), pemberontak dan pihak dalam sengketa (lihat kembali Kusumaatmadja dan Agus,2003). Kembali pada UU, yang merupakan wujud daripada ratifikasi perjanjian internasional oleh DPR, namun dalam kenyataannya dibatalkan secara sepihak oleh organ negara, yang bernama Mahkamah Konstitusi. Apakah dengan demikian, tidak bertentangan asas-asas umum dalam kebiasaan internasional, terutama berkaitan dengan kekuatan mengikatnya perjanjian antara negara yang berlaku dalam hukum internasional. Semua pendapat tersebut disampaikan, tidak lain dikarenakan menurut Mestoko (1985;31) bahwa pada umumnya traktat (perjanjian) ditaati oleh pihakpihak karena adanya adegium pacta sunt servanda (persetujuan antar negara harus dihormati). Bahkan asas pacta sunt servanda merupakan jus cogens (Starke,2008;66-67). Hal tersebut di atas, kemudian dipertegas kembali oleh Subagyo (2005;18) yang menyatakan bahwa para pihak terikat dan tunduk pada perjanjian sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan bersama. Bahkan dapatlah dikatakan seharusnya suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2000). Tidak lain, dikarenakan mengenai kejujuran atau itikad baik adalah faktor yang amat penting dalam hukum (Prodjodikoro,1995;56). Bahkan sebenarnya kita tidaklah perlu jauh-jauh untuk selanjutnya mencari dan menemukan prinsip-prinsip dasar terhadap kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Karena pada dasarnya, dalam sistem hukum kita pun sebenarnya sudah terdapat prinsip-prinsip, seperti apa yang sebenarnya berlaku dalam hukum internasional. Dengan demikian, sebenarnya prinsip-prinsip dalam sistem hukum kita, dalam kenyataannya tidaklah berbeda jauh dengan prinsip-prinsip umum, yang kemudian diakui kembali dalam hukum internasional, terutama terkait dengan mengikatnya perjanjian. Namun, haruslah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
612
diakui kemudian memang terjadi perbedaan, hanya saja perbedaan dalam tingkatan hukumnya. Di mana sistem hukum kita adalah bersifat nasional, dalam pada itu lebih mengutamakan hubungan hukum bersifat keperdataan. Ternyata dalam hukum perdata tersebut banyak dijumpai prinsip-prinsip yang sangat mirip, bahkan dapat dikatakan sama dengan ketentuan yang diakui keberadaannya, dikarenakan biasanya berlaku dalam hukum internasional. Seperti asas konsensualisme dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata (Bugerlijk reht) yang berbunyi Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hukum Romwi kemudian dikenal istilah Contractus Verbis Literis dan Contractus innominat, yang artinya suatu perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Dalam sistem hukum kitapun juga dikenal asas Pacta Sunt Sevanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Terdapatnya asas Pacta Sunt Servanda selanjutnya dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang. Bahkan, yang lebih tegas lagi ditentukan bahwa terkait dengan mengikatnya suatu perjanjian adalah dikarenakan adanya asas kebebasan untuk berkontrak. Asas kebebasan untuk berkontrak dapatlah dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (1) membuat atau tidak membuat perjanjian;(2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu secara lisan atau tertulis. Ini tidak lain dikarenakan, sebagai suatu perjanjian tentu selanjutnya mengikat pihak-pihak yang sebelumnya ikut terlibat secara langsung dalam membuat perjanjian tersebut, untuk selanjutnya melaksanakan segala isi daripada perjanjian tersebut. Bahkan dalam UU No 24 Tahun 2000, khususnya dalam ketentuan Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk Indonesia mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian internasional haruslah melalui cara-cara, seperti adanya Penandatangan; pengesahan; pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Dengan adanya cara-cara seperti tersebut di atas, maka dengan demikian tentunya Indonesia akan memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional sebagai hukum publik (Pasal 1 Ayat (1) UU No.24 Tahun 2000) yang karena diratifikasi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa sangatlah merugikan Indonesia, jika dikemudian hari ternyata ada suatu perjanjian internasional yang dibuat dengan negara lainnya, dalam kenyataannya dibatalkan oleh MK. Tentunya putusan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
613
MK terhadap undang-undang tersebut, disertai alasan dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945, ataupun dikarenakan melanggar hak konstitusional warga negara. Dengan adanya putusan MK tersebut, dapatlah kemudian dipastikan akan berdampak luas pada hubungan Indonesia dengan negara lainnya, terutama negara yang telah ikut terlibat dalam membuat perjanjian internasional tersebut dengan Indonesia. Bahkan dampak yang dapat terjadi terhadap pembatalan suatu perjanjian internasional, bisa juga melibatkan negaranegara lainnya di dalam dunia internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu (Kusumaatmadja dan Agoes,2003;117). Dalam ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004, khususnya dalam Pasal 18 menyatakan dengan jelas, terutama berkaitan apa-apa saja yang selanjutnya dapat menjadi penyebab batalnya suatu perjanjian internasional, yaitu sebagai berikut. a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; c. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; f. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional; g. Objek perjanjian hilang; h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional (Pasal 18 UU No.24 Tahun 2000). Dari kedelapan syarat untuk berakhirnya/batalnya perjanjian internasional sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas. Ternyata tidak ditentukan adanya suatu lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi, untuk memiliki kewenangan membatalkan perjanjian internasional. Paling banter ketentuan yang kemudian dapat ditemukan, berupa pembatalan sepihak perjanjian internasional oleh salah satu negara peserta, namun tindakan itupun untuk selanjutnya setelah adanya pembatalan sepihak tersebut, haruslah disusul kemudian dengan adanya suatu penerimaan dari pihak lain. Walaupun sellanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 huruf h UU No. 24 Tahun 2000 ditemukan pula kata hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Sehingga masih terbuka kesempatan untuk membatalkan suatu perjanjian internasional oleh negara yang telah mengadakan perjanjian tersebut, dengan alasan bahwa di dalam perjanjian tersebut terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Namun, argumen ini tentunya tidak mudah untuk dapat diterima begitu saja oleh negara lainnya, terutama mengatakan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
614
berkaitan dengan adanya suatu kerugian yang tentunya bersifat nasional. Apakah kemudian dapat dikatakan, misalnya jika perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh DPR dalam bentuk undang-undang, yang mungkin nantinya bisa saja materinya bertentangan dengan UUD 1945, merupakan salah satu alasan yang dapat dikatagorikan merugikan kepentingan nasional. Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut (Pasal 19 UU No.24 Tahun 2000). Beberapa teoritisi, misalnya Anzilotti, menyandarkan daya mengikat traktat-traktat kepada dalil latin pacta sunt servanda, atau dengan perkataan lain bahwa negara terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh traktat dengan itikad baik. Sekali negara mengikatkan diri pada perjanjian dalam suatu traktat, maka negara itu tidak berhak menarik diri dari kewajiban-kewajibannya tanpa persetujuan dari negara-negara peserta (Starke,2008584) (kursif penulis). Dengan demikian, tentunya pembatalan undang-undang yang pada dasarnya dibuat melalui bentuk perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi, tidak mungkin dapat begitu saja membebaskan Indonesia dari kewajiban internasional untuk selanjutnya melaksanakan semua isi perjanjian tersebut. Adanya ketentuan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, merupakan suatu ketentuan dari hukum nasional, tentunya kemudian akan berhadapan langsung dengan ketentuan hukum internasional. Jadi yang manakah selanjutnya memiliki kekuatan yang lebih mengikat atau dengan kata lain, manakah yang kemudian kedudukannya lebih tinggi. Tentunya bukan maksud daripada penulis, untuk ikut terjebak dalam jarring pertikaian antara penganut monoisme dan dualisme dalam hukum internasional. Namun merupakan suatu pelanggaraan yang bersifat terbuka terhadap hukum internasional, jika dalam kenyataannya suatu perjanjian yang telah dibuat oleh Indonesia, namun dikemudian hari dalam kenyataannya di batalkan oleh MK, sehingga dapat dipastikan akan menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. Memang jika dicermati kembali dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, terkait dengan adanya kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, ternyata di dalamnya memang tidak ada pembatasan yang dapat dikatakan jelas, khususnya berkaitan dengan materi apa saja yang kemudian dapat diuji oleh MK. Karena yang tampak di sana hanya berkaitan dengan bentuknya saja, yaitu undang-undang, di mana undangundang tersebut hanya dapat dibuat oleh DPR dan Presiden (Pasa 20 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian, walaupun dalam UUD 1945 tidaklah ditentukan secara eksplisit kewenangan MK untuk selanjutnya melakukan pengujian perjanjian internasional terhadap
I Gusti Ngurah Santika, SPd
615
UUD 1945, namun secara implisit sebenarnya MK memiliki kewenangan untuk melakukan tugasnya, berupa pengujian perjanjian internasional terhadap UUD 1945. Ternyata pengujian perjanjian internasional tersebut hanya dapat dilakukan oleh MK secara tidak langsung, yaitu setelah perjanjian internasional tersebut diratifikasi oleh DPR, sehingga nanti berubah bentuk menjadi undang-undang, kemudian tentunya setelah itu akan masuk dalam kualifikasi undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang tentu saja selanjutnya dapat diuji oleh MK apakah konstitusional atau tidak. Akhirnya International Court of Justice yang selanjutnya akan memutuskan, apakah suatu negara tertentu sudah mematuhi semua isi dari perjanjian tersebut. Yang mana jika keputusannya tidak dituruti kemudian oleh suatu negara dengan cara tidak memenuhi isi perjanjian internasional. Maka nantinya International Court of Justice selanjutnya akan meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk menindak negara yang ternyata tidak mematuhi putusan Mahkamah Internasional. Namun, dalam pengujian undang-undang yang ada hubungannya dengan perjanjian Internasional. Dapat kemudian dikatakan, bahwa hendaknya DPR maupun Presiden dalam membuat ataupun menyetujui suatu perjanjian internasional, terlebih dahulu meminta pendapat dari MK terkait dengan konstitusionalitas daripada perjanjian internasional tersebut. Tindakan tersebut dilakukan bertujuan untuk menghindari kelak dikemudian hari, jika adanya pengujian undang-undang yang merupakan tansformasi daripada perjanjian internasional tersebut. Maka dengan adanya tindakan tersebut tentunya akan semakin memperkecil kemungkinan suatu undang-undang yang merupakan hasil dari ratifikasi perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut, jika kita kembali membahas tentang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka pada dasarnya kita tidak dapat melepaskannya dari prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, adanya hierarki peraturan perundangundangan dapat membantu bagaimana membedakan kedudukan hukum, yaitu antara hukum yang kedudukannya lebih dengan kedudukan hukum yang lebih tinggi. Sehingga hukum yang kedudukannya lebih rendah tidaklah boleh bertentangan dengan hukum yang kedudukannya berada di atasnya. Karena hal tersebut merupakan prinsip utama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut perlu untuk dikemukakan, karena menurut pendapat penulis, yaitu berkenaan dengan keluarnya UU No. 12 Tahun 2011, dalam kenyataannya telah memasukan Ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya tepat di bawah UUD 1945. Sehingga secara teori mengkibatkan kesulitan bagi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan tugasnya, yaitu
I Gusti Ngurah Santika, SPd
616
menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (constitutional rivew). Tentunya pendapat tersebut dikatakan, jika seandainya kita terlebih dahulu mengetahui sehingga dapat memahami terkait dengan prinsip-prinsip dalam teori hierarki peraturan perundangundangan. Untuk itu, penulis akan kutipkan secara lengkap berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, yaitu BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 7 1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (kursif penulis). Pada mulanya penulis hanya mengeketahui berkaitan dengan undang-undang yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu UU No.10 Tahun 2004. Namun, pada saat mengikuti sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di STIE Singaraja, tim penyaji yang merupakan anggota MPR RI tersebut, ternyata mengajukan pertanyaan berkenaan suatu undang-undang yang mengatur berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketika penulis langsung menjawab pertanyaan dari tim penyaji tersebut, yang pada dasarnya waktu itu menanyakan masalah undang-undang yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka penulis kemudian menjawabnya dengan menyebutkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, terhadap jawaban tersebut, tim penyaji menyatakan bahwa UU No. 10 Tahun 2004 sudah tidak berlaku, karena untuk sekarang dengan keluarnya peraturan baru yang selanjutnya menggantikan UU No. 10 Tahun 2004, yaitu dengan UU No. 12 Tahun 2011, yang tentunya juga mengatur hal sama. Pada waktu itu, tim penyaji menyatakan bahwa dalam undang-undang baru tersebut,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
617
pembentuk undang-undang telah kembali memasukan Ketetapan MPR, ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang posisinya berada tepat di bawah UUD 1945. Dengan adanya pernyataan tersebut di atas tadi, jelas kemudian penulis merasa kaget bahkan merasa heran, tidak lain dikarenakan setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945, sebenarnya MPR menurut UUD 1945 tidaklah lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur seperti sebelumnya. Karena menurut UUD 1945 pasca amandemen, MPR hanya dapat membuat satu ketentuan saja yang bersifat mengatur, yaitu dalam bentuk Perubahan UUD 1945, bukannya berbentuk ketetapan seperti sebelumnya. Bahkan, setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945, pada dasarnya UUD 1945 telah menegaskan prinsip berkaitan dengan kedudukan undang-undang yang ditentukan tepat berada langsung di bawah UUD 1945. Bahkan, ditambah untuk sekarang ini telah adanya sebuah lembaga peradilan konstitusi (constitutional court), yaitu MK, yang kemudian terlihat jelas dengan menjalankan tugas-tugasnya utamanya berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Bahwa prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sudah jelas digariskan dalam UUD 1945, yakni kedudukan undangundang tepat berada di bawah UUD 1945 itu sendiri. Hal mana tampak jelas dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam UUD 1945, tepatnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang mana dinyatakan MK bertugas untuk menguji undang undang terhadap UUD 1945 (yudicial review, constitutional review or toetsingricht). Logikanya di sini adalah jika Tap MPR kedudukannya tepat berada di bawah UUD 1945, apakah ketentuan demikian tidak bertentangan secara diametral dengan UUD 1945. Di mana pada dasarnya UUD 1945, hanya mengenal bentuk peraturan pelaksanaannya. yaitu dalam bentuk UU, khususnya menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Tidak lain, dikarenakan dengan jelas telah ditentukan bahwa peraturan lebih lanjut untuk mengatur UUD 1945, telah diserahkan kepada UU yang memang berkedudukan di bawahnya. Ketentuan tersebut adalah sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan, yang pada dasarnya menyatakan bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah, harus berdasar, bersumber dan berlaku pada peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Jadi peraturan yang kedudukannya lebih tinggilah, yang kemudian memberikan sumber, bagi berlakunya peraturan yang kedudukannya lebih rendah. Karena tanpa adanya sumber norma yang berkedudukan sebagai dasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi, maka dapatlah dipastikan peraturan yang kedudukannya lebih rendah, tentunya tidak akan memiliki dasar yang kuat. Bahkan, dalam negara hukum konsep hierarki peraturan perundang-undangan adalah sangat prinsip. Dengan demikian, dimanakah letak dasar kewenangan daripada UU No. 12 Tahun 2011, yang dalam salah
I Gusti Ngurah Santika, SPd
618
satu ketentuannya telah memberikan tugas kepada MPR untuk membentuk suatu ketetapan. Padahal ketetapan MPR tersebut, posisinya tepat berada di bawah UUD 1945, sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang tentunya normanya abstrak sehingga mengikat umum? Padahal yang sebenarnya memberikan legalitas terhadap kedudukan hulum terhadap ketetapan MPR tersebut, yaitu DPR dan Presiden dalam bentuk produk hukumnya yang dinamakan undang-undang, khusus UU No. 12 Tahun 2011. Keberatan yang penulis ajukan berkaitan dengan adanya Ketetapan MPR, yang kemudian dimasukan menjadi salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Keberatan selanjutnya terhadap Ketetapan MPR tersebut, terutama dikarenakan oleh posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang kedudukannya tepat berada di bawah UUD 1945 atau di atas undang-undang. Dengan demikian, UU No. 12 Tahun 2011, pada dasarnya telah memberikan kewenangan yang lebih tinggi dari UU kepada ketetapan MPR, yang merupakan produk hukum dibentuk oleh MPR. Sehingga, menurut pendapat penulis sudah seharusnya kedudukan Ketetapan MPR tidak dapat berada di bawah UUD 1945, dikarenakan sebenarnya pelaksana langsung dari ketentuan dalam UUD 1945, yaitu dalam bentuk undang-undang. Terjadinya perubahan kewenangan MPR seperti sekarang ini, tidak lain dikarenakan berkaitan dengan adanya perubahan kedudukan MPR. Karena untuk sekarang MPR bukan lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat, yang bertugas untuk menetapkan GBHN seperti sebelum amandemen. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, MPR tentu tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan suatu produk hukum yang bersifat mengatur ke luar, selain dalam bentuk bentuk bakunya, yaitu Perubahan UUD 1945. Artinya di sini, dapat saja untuk selanjunya MPR mengeluarkan suatu produk hukum dengan bentuk ketetapan MPR. Namun, hanya saja ketetapan MPR tersebut berfungsi secara internal, yang berarti hanya diperkenankan untuk mengikat ke dalam bukan ke luar, misalnya saja berkaitan dengan pengaturan tata tertib persidangan MPR, maka untuk itu dapat selanjutnya ditetapkan melalui Ketetapan MPR. Berkaitan dengan Ketetapan MPR, Asshiddiqie (2004;205) menyatakan bahwa MPR tidak boleh dan tidak akan lagi menetapkan produk hukum yang bersifat mengatur (regeling), kecuali dalam bentuk UUD atau Perubahan UUD. Namun, kewenangan MPR untuk mengeluarkan produk hukum yang tidak bersifat mengatur tetap dapat dipertahankan. Bahkan, penulis berpendapat bahwa dengan menempatkan Ketetapan MPR di atas UU, maka secara tidak langsung telah merubah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang kemudian ketentuan tersebut berbunyi menjadi MK berwenangan menguji UU terhadap Ketetapan MPR. Dengan demikian, adanya Ketetapan MPR tersebut jelas-jelas sangat bertentangan secara konstitusional dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam pada itu,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
619
bagaimanakah selanjutnya berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut tentang pengujian pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang diatur kembali dalam bentuk UU, terutama kewenangan MK tersebut di atas. Jika lihat kembali dalam ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, sangat jelaslah dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa MK hanya menguji UU terhadap UUD 1945, bukan menguji UU terhadap Tap MPR, ataupun menguji Tap MPR terhadap UUD 1945. Mengapa dalam UU MK, tidak ada pengaturan mengenai pengujian undang-undang terhadap Ketetapan MPR, maupun pengujian Ketetapan MPR terhadap UUD 1945? Lahirnya pertanyaan ini didasari oleh teori hierarki peraturan perundangundangan, yang pada dasarnya menyatakan, peraturan yang kedudukannya lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 2011, yang mengatur tentang hierarki peraturan perundangundangan sudah jelas menentukan posisi daripada Ketetapan MPR berada langsung di bawah UUD 1945, sehingga secara tidak langsung berimplikasi pada kedudukan UU berada tepat di bawah ketetapan MPR. Jika saja ketentuan pengaturan sebagaimana dimaksudkan di atas (pengujian undang-undang terhadap MPR atau ketetapan MPR terhadap UUD 1945), secara tegas dicantumkan ke dalam UU MK, yang sebenarnya telah ditugaskan oleh UUD 1945 untuk mengatur pengujian undang-undang terhadap UUD, maka terlihat secara eksplisit ketentuan tersebut akan benar-benar bertentangan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun, dengan tidak dicantumkan secara ekplisit, terkait kewenangan pengujian Ketetapan MPR terhadap UUD 1945, maupun berkenaan pengujian UU terhadap Ketetapan MPR, tentunya kesimpulan yang selanjutnya diperoleh, tidaklah mengurangi maksud daripada ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, khususnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Bahkan sudah sangat jelas maksud dari ketentuan ayat (2) dari Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa ketetapan MPR memiliki kedudukan lebih tinggi jika selanjutnya ditinjau kembali dari hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tentunya secara langsung dapat dikatakan bahwa materi Ketetapan MPR tersebut lebih tinggi kedudukannya daripada UU. Oleh karena itu, untuk sekarang ini seharusnya, Ketetapan MPR tidak dapat dimasukan kembali ke dalam salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, apalagi kedudukannya tepat berada di bawah UUD 1945. Ditambah alasan lain lagi bahwa dikarenakan dengan dikeluarkannya Tap MPR No. I Tahun 2003 tentang Peninjauan Tap MPRS dari tahun 1960 sampai tahun 2002. Memang dalam kenyataannya masih ada beberapa ketentuan, berupa Ketetapan MPR yang masih berlaku hingga saat ini. Pelaksanaan atas perintah Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945, telah dituangkan kembali di dalam Tap MPR No. 1/MPR/2003 yang selanjutnya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
620
mengelompokan sebanyak 139 Tap MPR/S (1960-2002) ke dalam status yang berbedabeda: ada yang dicabut, ada yang tetap berlaku sebagai pedoman, ada yang berlaku sampai keluarnya UU yang menggantikannya, ada yang berlaku sampai habisnya masa tugas pejabat/lembaga negara berdasarkan hasil pemilu tahun 2004, ada yang dinyatakan berlaku sampai isi/penugasannya diselesaikan secara tuntas, dan ada yang dinyatakan tak memerlukan tindakan hukum karena sudah selesai dan bersifat einmalig (Mahmud MD,2011;54). Dengan demikian, seharusnya MPR untuk sekarang ini, tidaklah memiliki kewenangan untuk kemudian menetapkan produk hukum, yang pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat ke luar. Pendapat ini kemudian didukung kembali, oleh Budiardjo (2008;350) yang pada hakekatnya menyatakan MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN, MPR juga tidak lagi mengeluarkan TAP MPR kecuali yang menetapkan wapres menjadi presiden dan memilih wapres bila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Jadi, MPR tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang mengikat umum, hal mana dikarenakan peraturan tersebut tentunya mengandung norma abstrak. Melainkan MPR sekarang ini hanya dapat membentuk ketetapan, yang di dalamnya berisi norma konket, sehingga hanya dapat ditujukan secara jelas, mengenai objek yang dikenai oleh norma tersebut, seperti Wakil Presiden, yang dengan adanya ketetapan MPR tersebut, kemudian ditentukan untuk diangkat menggantikan Presiden. Permasalahan lainnya yang kemudian dibawa oleh UU No.12 Tahun 2011 secara teori adalah kesulitan yang mendasar untuk melakukan pengujian peraturan perundangundangan, yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Tidak lain, dikarenakan pada dasarnya hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011, ternyata tampak terlihat dengan sangat jelas menyatakan kedudukan Ketetapan MPR tepat berada di bawah UUD 1945, sedangkan untuk kedudukan UU ternyata berada di bawah ketetapan MPR. Pertanyaannya adalah bagaimana jika suatu hari dalam kenyataannya terjadi pertentangan antara ketetapan MPR dengan UUD 1945. Dengan demikian, lantas siapakah yang kemudian memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadapnya? Jika, jawaban terhadap pertanyaan tersebut di atas adalah MK, maka jawaban tersebut jelaslah sangat tidak tepat sekali. Karena baik dalam UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 24C ayat (1), maupun dalam ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No.18 Tahun 2011 yang mengatur lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi, ternyata MK hanya melakukan tugasnya berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD, bukannnya bertugas menguji ketetapan MPR terhadap UUD 1945. Bahkan, jika pandang kembali terutama dari prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, maka seperti yang diatur dalam UU No. 12
I Gusti Ngurah Santika, SPd
621
Tahun 2011, seharusnya undang-undang hanya dapat diuji, jika bertentangan dengan Ketetapan MPR. Lantas pertanyaannya yang diajukan di sini, yaitu siapakah yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Ketetapan MPR, jika suatu saat ada suatu undang-undang yang kemudian nyata-nyata bertentangan dengan Ketetapan MPR? Tentunya ini adalah sebuah problem yang dapat dipandang serius, untuk selanjutnya dipecahkan secara bersama-sama, di manakah sebenarnya letak daripada permasalahannya, yang dapat saja kemudian menyebabkan secara teori berkaitan dengan pengujian undangundang terhadap UUD 1945 terganggu. Beberapa solusi akan penulis coba untuk tawarkan terkait dengan permasalahan pengujian peraturan perundang-undangan pasca keluartnya UU No. 12 Tahun 2011. Untuk solusinya yang pertama, berkaitan dengan pengujian peraturan undang-undang terhadap UUD 1945 agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari, yaitu hanya dapat dilakukan dengan tidak meletakan Ketetapan MPR tersebut di atas UU, tetapi meletakan posisinya sederajat dengan kedudukan undang-undang. Sehingga dapatllah kemudian dikatakan kedudukan Ketetapan MPR tersebut adalah sama dengan kedudukan undang-undang. Dengan demikian, jika dalam kenyataannya Ketetapan MPR tersebut, ada ketentuan yang nyata-nyata bertentangan secara diametral dengan UUD 1945 atau melanggar hak-hak konstitusional warga negara, maka MK dapat saja kemudian membatalkan ketetapan MPR tersebut. Bahkan, pendapat inipun selanjutnya dapat kita temukan kembali dalam buku Prof. Jimly Asshiddiqie, yang berjudul Prihal UndangUndang (2006), yang pada dasarnya menjelaskan bahwa dalam ketetapan MPR No. 1 Tahun 2003 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS dari Tahun 1960 sampai dengan 2002. Bahkan, di dalam salah satu ketetapan MPR tersebut, ada ketentuan yang kemudian menyatakan dengan secara sengaja menurunkan derajat Ketetapan MPR tersebut, sehingga kedudukannya menjadi setara dengan UU. Namun, untuk sekarang ini, penulis berpendapat terkait dengan solusi yang diberikan di atas adalah kurang memuaskan untuk memecahkan terkait dengan permasalahan pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama pasca keluarnya UU No. 12 Tahun 2011. Berdasarkan paparan tersebut di atas, terkait dengan permasalahan pengujian peraturan perundang-undangan, terlebih lagi setelah ditentukannya Ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, yang kedudukannya tepat berada di bawah UUD 1945. Maka untuk itu, penulis akan mencoba untuk memahami ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yang telah meletakan Ketetapan MPR di bawah UUD 1945. Dalam pada itu, penulis memiliki dugaan kuat bahwa dengan memasukan kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang, yaitu oleh DPR dan Presiden.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
622
Sebenarnya hanyalah merupakan suatu kesepakatan politik saja di antara kedua lembaga tersebut, dengan tujuan yang sesungguhnya tidaklah jelas atau paling tidak, sangat sulit untuk kemudian dipahami secara ilmiah. Sehingga dengan masuknya ketetapan MPR tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tentunya telah membawa suatu kecurigaan yang bersifat mendasar. Di mana menurut penulis, dikarenakan untuk selama ini kita mengetahui bahwa berkaitan dengan sepak terjang daripada MK dalam tugasnya untuk mengawal konstitusi, telah pula banyak membatalkan ketentuan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Mungkin dengan banyak ketentuan undang-undang yang sebelumnya dibatalkan oleh MK, secara tidak langsung telah menyebabkan DPR dan Presiden kewalahan dalam membentuk undang-undang, yang pada dasarnya banyak sekali memuat kepentingan-kepentingan mereka, yang tentunya sangat bertentangan dengan UUD 1945, di samping dapatlah kemudian dipastikan telah merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Padahal hanya dengan lima orang hakim dari jumlah keseluruhan sembilan orang hakim MK, kemudian dalam kenyataannya dapat membatalkan sebuah UU, yang merupakan keputusan bersama antara DPR dengan jumlah anggotanya sebanyak 560 anggota dan Pemerintah. Dengan demikian, telah terbukti dengan banyaknya undangundang ternyata dibatalkan oleh MK, yang tentunya merugikan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga berarti juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan pendapat tersebut diatas merupakan alasan penulis, yang mungkin kira-kira menyebabkan DPR dan Pemerintah memasukan kembali Ketetapan MPR, sebagai salah satu bentuk hukum ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Di mana sebelumnya terkait dengan adanya Ketetapan MPR, ternyata sebagian ahli hukum berpandangan bahwa Tap MPR sebelum perubahan UUD 1945, sebagai barang haram. Dengan begitu, keluarnya UU No. 12 Tahun 2011, yang kemudian disertai dengan memasukan ketetapan MPR kembali ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan secara tidak langsung telah mengkebiri kewenangan MK, yang ditugaskan menjaga konstitusi. Agar untuk ke depannya MK tidak mengalami lagi kesulitan, terutama jika dipandang dari sudut teoritis berkaitan dengan tugasnya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka untuk itu diperlukan jalan keluar yang baik. Jangan sampai kewenangan MK tersebut dikebiri, oleh dikarenakan hadirnya ketetapan MPR ditengah-tengah sistem ketatanegaraan Indonesia, yang kemudian secara tidak sengaja menjadi penghalang hubungan antara UUD 1945 dengan undang-undang. Oleh karena itu, UU No. 12 Tahun 2011 tersebut sebaiknya, jika memang jelas-jelas maksud dari dimasukannya Ketetapan MPR sebagaimana dugaan penulis di atas, sebaiknya berkenaan dengan masalah tersebut diajukan saja ke MK untuk dibatalkan. Mengapa ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang dibatalkan bukannya
I Gusti Ngurah Santika, SPd
623
Ketetapan MPR? Hal mana tidak lain dikarenakan, MK pada dasarnya memang tidak memiliki kewenangan untuk menguji Ketetapan MPR terhadap UUD 1945, dikarenakan MK hanya ditentukan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Jadi, dengan memasukan ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang kemudian hanya dengan didasari oleh UU No 12 Tahun 2011, sebenarnya tidaklah memiliki landasan hukum yang kuat. Karena tentunya landasan hukum dari adanya bentuk Ketetapan MPR hanya terdapat dalam undang-undang, sedangkan untuk UU tersebut dibuat oleh DPR dan Presiden melalui kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945 (Pasal 20 ayat (2)). Sedangkan untuk MK, dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945, bertujuan untuk melindungi konstitusi dari kehendak politik yang pada dasarnya bertentangan dengannya, terutama dalam bentuk undang-undang yang dibentuk oleh lembaga politik. Tidak lain, karena pada hakekatnya undang-undang tersebut, sebenarnya merupakan perintah dari UUD 1945, untuk kemudian mengatur ketentuan lebih lanjut masalah yang memang belum sempat untuk diatur dalam UUD 1945, baik dalam/dengan bentuk undang-undang. Bahkan, yang lebih anehnya lagi di sini adalah dikarenakan tidak mungkin suatu lembaga negara, yang selanjutnya memberikan kewenangan untuk kemudian membentuk peraturan tertentu kepada lembaga negara lain. Namun, dalam kenyataannya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan tersebut, ternyata kedudukan peraturan yang dibentuknya kemudian, berada di atas produk hukum lembaga yang sebelumnya memberikan kewenangan kepadanya. Dengan kata lain, peraturan yang dibentuk oleh lembaga penerima delegasi dari lembaga pemberi delegasi, ternyata kedudukan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang penerima delegasi tersebut, lebih tinggi daripada lembaga yang memberikan kewenangan tersebut, yaitu DPR dan Presiden. Misalkan, dimana DPR dan Presiden memberikan kewenangan kepada MPR untuk membentuk peraturan hukum yang sifanya mengikat umum dalam bentuk Ketetapan MPR, yang dinyatakan dengan tegas dalam UU No. 12 Tahun 2011. Kemudian ternyata Ketetapan MPR tersebut, yang merupakan kewenangan delegasi daripada DPR dan Presiden yang terdapat dalam UU, dalam kenyataannya lebih tinggi kedudukannya daripada bentuk hukum lembaga pemberi delegasi (DPR dan Presiden), yaitu lembaga pembentuk undang-undang. Jadi, sebenarnya UU No. 12 Tahun 2011, di dalamnya telah mengandung kontradiksi tersendiri terkait pengaturan pemberian kewenangan kepada MPR, untuk kemudian membentuk Ketetapan MPR yang pada dasarnya mengikat umum. Sehingga seolah-olah terlihat bahwa DPR dan Pemerintah merendahkan dirinya sendiri, dihadapan lembaga negara yang diberinya wewenang untuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
624
membentuk peraturan hukum. Dengan demikian, DPR dan Presiden telah memberikan lebih daripada yang mereka miliki kepada MPR, terkait dengan kedudukan hukum Ketetapan MPR tersebut, dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ada satu lagi permasalahan yang menurut penulis pantas dan penting untuk kemudian dikemukakan di sini, berkaitan dengan adanya kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (constitutional rivew). Permasalahan yang mungkin saja nantinya timbul dalam pengujian undang-undang menurut penulis, adalah pengujian formal yang dimiliki oleh MK, di mana jika saja kita dikaitkan kembali dengan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege(Moeljatno,2009;25), asas hukum tersebut merupakan suatu asas yang mendasari seseorang untuk selanjutnya dapat diajukan ke muka pengadilan, jika sebelumnya benar-benar bersalah dengan ketentuan melanggar undang-undang. Bahwa ketentuan sanksi pidana ini tidak boleh berlaku surut (geen terug warkende kracht) (Prodjodikoro,2008;42). Dengan kata lain, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan telah ada sebelumnya (Hamzah,2005;3). Sehingga untuk itu setiap tindakan itu harus sah menurut aturan hukum yang telah ada (Mahmud MD,2001;87). Oleh karenanya, dalam melakukan penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, tentunya harus pula berdasarkan undang-undang, yang ditentukan dengan tegas pasal-pasal apa saja yang sesuai atau pantas untuk didakwakan terhadap pelakunya di depan pengadilan. Nah!!! apa kiranya relevansi penulis menyatakan berkaitan dengan masalah ini? Permasalahan yang mungkin saja timbul dari pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, adalah hapusnya pasal-pasal yang dijadikan dasar penuntutan oleh jaksa penuntut umum, karena telah dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi lewat uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Jika kemudian dikaitkan kembali dengan adanya pengujian materiil (isi), yang tentunya hanya menguji salah satu pasal atau beberapa pasal dari undang-undang, maka bisa jadi atau mungkin tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Tidak lain, dikarenakan biasanya jaksa sebagai penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa, tidak hanya kemudian mendasarkan penuntutannya pada satu pasal saja. Biasanya, penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengenakan dua pasal atau lebih, selanjutnya mengklasifikasikan pasal tersebut menjadi pasal primer dan subsider yang tentunya akan berbeda antara satu pasal dan pasal yang lainnya, berkenaan dengan macam beratnya ancaman hukuman, yang akan nantinya diterima oleh terdakwa, apabila dikemudian hari diputuskan oleh pangadilan. Namun, yang menjadi masalah adalah jika suatu saat terjadi penuntutan terdakwa oleh jaksa penuntut umum, namun dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
625
kenyataannya pada waktu yang bersamaan, terjadi pula pengujian formal atas undangundang terhadap UUD 1945. Padahal dalam kenyataannya beberapa pasal yang terdapat undang-undang tersebut sedang dilakukan pengujian oleh MK, namun ternyata dijadikan dasar penuntutan terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Setidak-tidaknya pasal-pasal dijadikan dasar sebagai penuntutan terdakwa oleh penuntut umum tersebut, bersumber dari undang-undang yang sedang dilakukan pengujian terhadap UUD 1945 berkaitan dengan bentuk/prosedur pembentukannya di MK. Ternyata dalam perjalanannya MK tersebut, tidaklah menutup kemungkinan bisa saja kemudian membatalkan undang-undang dimaksud, yang sebenarnya pada waktu itu juga dijadikan dasar penuntutan terdakwa di pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, tentunya akan menyebabkan terjadinya kekosongan peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan landasan/dasar dalam melakukan penuntutan oleh jaksa terhadap terdakwa di hadapan pengadilan. Dengan begitu, tindakan yang mungkin sebelumnya merupakan suatu tindakan pidana karena ditentukan telah melanggar hukum, sebagian pakar kemudian menggunakan istilah onrechtmatigedaad, tetapi untuk sebagian lagi menggunakan istilah wederrechtelijk (Marpaung,2009;44). Namun, setelah adanya keputusan MK, berupa pembatalan terhadap undang-undang yang sebenarnya dijadikan dasar penuntutan oleh jaksa terhadap terdakwa, maka tindakan terdakwa tersebut berubah menjadi tindakan yang benar, karena tidak ada larangan lagi dari suatu undang-undang untuk berbuat seperti itu. Hal mana tentunya akan berbeda, jika dalam kenyataannya keputusan pengadilan lebih dahulu ketimbang putusan MK yang datang kemudian. Jika suatu pengadilan sudah memutuskan terdakwa dengan putusan bersalah, maka tentunya putusan MK atas pengujian undang-undang yang sebelumnya dijadikan dasar penuntutan terhadap terdakwa oleh jaksa, tentunya tidak akan mempengaruhi putusan pengadilan tadi. Walaupun dulunya undang-undang yang sebelumnya dijadikan dasar putusan daripada pengadilan, untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, telah dibatalkan MK. Namun, merupakan suatu ketidakadilan yang sangat besar, jika saja nantinya dalam melakukan kejahatan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dapat dilakukan lebih daripada satu orang, yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut (misalnya deelneming dalam KUHP tepatnya dalam Pasal 55 dan 56). Namun, karena misalnya keadaan salah satu tersangka sebagai pelaku kejahatan ternyata sakit, maka untuk itu tersangka yang sakit tersebut belumlah dapat dilakukan proses hukum, sedangkan temannya yang satunya ternyata sudah mendapatkan putusan dari pengadilan. Tapi kemudian dengan adanya keputusan dari MK tersebut, telah pula menyebabkan tindakan yang sebelumnya menurut undang-undang tersebut adalah ilegal. Namun setelah adanya keputusan dari MK terhadap undang-undang itu, kemudian tindakan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
626
tersebut akan berubah menjadi legal. Sehingga mau tidak mau, orang yang tadinya belum diadili tersebut, tidak mungkin dapat lagi diajukan ke hadapan pengadilan, karena tidak ada lagi undang-undang yang dapat melarang perbuatan seperti itu. Padahal mungkin saja temannya, yang pada saat melakukan perbuatan tersebut bersama-sama, sudah meringkuk lebih dulu dalam tahanan. Tidak lain dikarenakan sudah diputuskan oleh pengadilan, sedangkan teman yang lainnya mungkin dapat melenggang dengan bebas. Karena dengan adanya putusan dari MK yang pada dasarnya telah menghapus dasar peraturan dari perbuatan yang dulunya merupakan perbuatan melanggar hukum, kemudian berubah menjadi perbuatan yang legal. Menurut penulis, ada satu jalan agar masalah tersebut tidak terjadi dikemudian hari, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk selanjutnya mengajukan constitutional question. Dengan adanya constitutional question, dimana seorang hakim yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang berlaku (Hamidi dan Lutfi,2010;236). Padahal undang-undang tersebut dijadikan dasar penuntutan terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan. Dan jika memang merasa bahwa hakim masih ragu-ragu tentang konstitusionalitas daripada suatu undang-undang, maka hakim tersebut dapat saja mengajukan pertanyaan kepada MK. Sedangkan terkait dengan masalah perkara yang sedang ditangani dipangadilan umum, dihentikan terlebih dahulu sampai dengan adanya keputusan dari MK. Masalah inipun kemudian sebenarnya dapat saja dipecahkan dengan mencarikan jalan keluar yang baik. Jika saja dimungkinkan dengan memanfaatkan daripada ketentuan Pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004, yang pada dasarnya mengatur pengujian peraturan perundang-undangan antara MK dan MA. Jadi, terkait dengan masalah tersebut, sebenarnya dapat juga untuk kemudian diterapkan, dikarenakan pada dasarnya MK sedang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, setidaknya MA sendiri telah mengetahui hal tersebut. Kemudian pengadilan negeri yang bertugas mengadili berkaitan dengan perkara pidana sebagaimana dimaksudkan di atas, merupakan salah satu badan peradilan yang kedudukannya berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum. Yang tentunya terkait dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Mahkamah Agung dapat saja segera memerintahkan kemudian, untuk memberhentikan sementara waktu, terkait dengan proses perkara pidana yang sedang berlangsung di pengadilan negeri. Proses berperkara dalam peradilan pidana dapat dilanjutkan kemudian, namun setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi, terkait dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, karena undang-undang tersebut dijadikan dasar dalam penuntutan oleh jaksa terhadap
I Gusti Ngurah Santika, SPd
627
terdakwa dalam peradilan konstitutionalitasnya.
pidana
dinilai
oleh
hakim
perlu
diuji
kembali
Persengketaan Lembaga Negara Selain permasalahan tersebut di atas, menyangkut kewenangan MK dalam memutus persengketaan lembaga-lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Banyak pihak yang kemudian berpendapat, bahwa MK merupakan lembaga yang super power, hal mana dikarenakan kedudukan MK yang memiliki kewenangan untuk selanjutnya memutuskan persengketaan yang terjadi antara lembaga negara, berkaitan dengan kewenangan memang diberikan oleh UUD 1945. Bahkan, keputusannya tersebut telah ditentukan bersifat final dan mengikat, serta tidak mungkin untuk dapat dilawan kembali dengan jalan apapun. Dengan demikian, terlihat bahwa MK kedudukannya lebih tinggi, apabila dibandingkan kemudian dengan lembaga negara lainnya, terutama lembaga yang sedang bersengketa, terkait dengan kewenangannya yang merasa diambil alih oleh lembaga negara lainnya dalam UUD 1945. Bahkan, lembaga negara lain yang bersengketa tidak memiliki kekuatan apapun untuk selanjutnya melawan putusan MK tersebut. Hal mana dikarenakan putusan MK, terkait dengan kewenangannya untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD1945, merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada lagi mekanisme yang kemudian dapat digunakan, untuk kembali melawan putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut. Namun, dalam UU No. 24 Tahun 2003, telah ditentukan lembaga-lembaga mana saja, yang kemudian dapat bersengketa terkait dengan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD 1945. Namun, dalam kenyataannya ada lembaga yang kemudian dikecualikan dalam persengketaan kewenangan lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung (supreme court). Berkaitan dengan tidak masuknya salah satu lembaga negara, yaitu MA, sebagai salah satu objek yang dapat saja bersengketa dengan kewenangan lembaga negara lainnya, seperti yang ditentukan dalam UUD 1945. Apakah sebenarnya yang kemudian menjadi dasar serta melatar belakangi pemikiran daripada UU No. 24 Tahun 2003 untuk tidak memasukan MA, sebagai salah satu pihak yang dapat saja bersengketa dengan lembaga negara lain, terutama berkaitan dengan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945. Apakah benar MA tidak mungkin dapat bersengketa dengan lembaga negara lain berkaitan dengan tugas dan fungsinya yang telah diberikan oleh UUD 1945? Bagaimana jika antara MA dan KY yang tentunya memiliki tugas yang sampir sama, terutama terkait dalam bidang pengawasan hakim, apakah tidak ada kemungkinan untuk kemudian bersengketa di
I Gusti Ngurah Santika, SPd
628
antara kedua lembaga negara? Dalam masalah tersebut, Latif (2009;150) kemudian menyatakan bahwa problematik yang muncul adalah bagaimana jika MA sebagai pihak dalam persidangan di MK. Pasal 65 UU No 24 Tahun 2003 menentukan bahwa MA tidak dapat jadi pihak dalam sengketa kewenangan di MK. Padahal Presiden dan DPR tidak dibatasi demikian. Alasan pembatasan tersebut menurut Asshiddiqie, karena kasasi bersifat final, masa diadili lagi di lembaga lain. Pembatasan ini juga dimaksudkan untuk jawaban pertanyaan bagaimana jika MA sengketa dengan MK, mengapa hanya MK yang memutuskan sendiri? Inilah yang menjadi pertanyaan penulis, apa menjadi dasar pemikiran bahwa MA tidak termasuk objek keputusan MK dalam persengketaan mengenai kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945? Sedangkan bisa saja nantinya MK bersengketa dengan DPR, berkaitan tugas dan kewenangan yang telah ditentukan dalam UUD 1945, kalau itu terjadi siapakah yang selanjutnya akan memutuskan. Hal mana dapat diketahui, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 UUD 1945, sebenarnya telah memberikan kewenangan kepada Presiden, untuk kemudian menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, yang kemudian untuk selanjutnya harus diajukan kembali kepada DPR pada sidang berikutnya, untuk diputuskan apakah akan ditetapkan sebagai undang-undang atau tidak. Dalam penetapan Perpu, kita mengetahui bahwa Perpu yang telah ditetapkan oleh Presiden tersebut, tentunya memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, terutama terkait dengan materinya. Pernyataannya tersebut sangat jelas dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum di hapus, maupun oleh UU No. 12 Tahun 2011 tepatnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Paling tidak, walaupun berbentuk peraturan pemerintah, namun isinya setingkat dengan undang-undang. Bisa saja suatu hari nanti, ternyata ada suatu Perpu yang terindikasi melanggar UUD 1945, misalnya terkait dengan hak konstitusional warga negara, sedangkan dalam UUD 1945 telah ditentukan bahwa DPR yang berwenang untuk melakukan pengujian atas Perpu tersebut. Namun, karena berbagai alasan yang kemudian dipandang oleh MK bahwa dalam kenyataannya Perpu tersebut memang belum dapat diujikan ke DPR, terutama karena adanya berbagai alasan politik. Dengan alasan tersebut, bisa saja dalam kenyataannya MK kemudian memutuskan bahwa Perpu tersebut harus dibatalkan, karena jelas-jelas secara diametral bertentangan dengan konstitusi. Nah!!! jika demikian yang terjadi, apakah telah dapat dikatakan terjadi persengketaan antara DPR dan MK, berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam hal pengujian Perpu seperti tersebut di atas. Jika memang dapat dikatakan telah terjadi persengketaan kewenangan kelembagaan negara sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Lantas siapakah yang kemudian diberikan kewenangan untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, apakah tetap pada MK,
I Gusti Ngurah Santika, SPd
629
yang dalam permasalahan ini kedudukannya dapat dikatakan merupakan salah satu lembaga yang sedang bersengketa berkaitan dengan kewenangannya menurut UUD 1945. Tentunya terkait dengan masalah tersebut, ada yang kemudian berpendapat, bahwa tidak ada yang dapat menjadi hakim baik dalam perkaranya sendiri (nemo judex ideoneus in propria causa). Bahkan dalam permasalahan ini hakim MK wajib untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan yang bersangkutan (excussatie verschoningsrecht). Kewenangan MK Dalam Pemutusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Permasalahan timbul kemudian selain seperti apa yang disebutkan di atas, karena ada satu lagi permasalahan, yang berkaitan dengan kewenangan daripada MK dalam memutus hasil pemilihan umum kepala daerah, sebenarnya menurut penulis juga memiliki masalah. Karena dalam hal ini menurut penulis tidaklah memiliki landasan hukum yang kuat. Dikarenakan kata dipilih secara demokratis dalam ketentuan ayat (4) dari Pasal 18 UUD 1945, belumlah tentu dapat dikatakan kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan jika dilihat kemudian dalam Bab VII B, khususnya ketentuan Pasal 22E bahwa pilkada jelas bukanlah rezim pemilu, seperti apa yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, untuk kemudian diputus oleh MK secara final. Dikarenakan menurut UUD 1945, pemilu hanya untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Di manakah kemudian letak landasan hukum MK untuk selanjutnya memutus PHPU kepala daerah? Menurut penulis letak landasan hukum MK dalam memutus PHP kepala daerah adalah terletak dalam UU Pemerintahan Daerah yang sebenarnya dulu merupakan kewenangan daripada MA (lihat UU No. 32 Tahun 2004) kemudian selanjutnya dipindahkan ke MK (lihat UU No. 12 tahun 2008 jo UU 22 Tahun 2007). Hal mana dapatlah kemudian disimpulkan bahwa wewenang yang diperoleh MK dalam memutus PHPU, nyatanya bukan berasal dari UUD 1945, melainkan hanya di dapat dari UU saja. Apakah berkaitan dengan permasalahan ini, MK dapat kemudian memutuskan PHPU kepala daerah, walaupun pada dasarnya tidaklah berlandaskan pada UUD 1945?. Apakah kata pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dapat disamakan dengan pemilihan umum secara langsung kepala daerah yang sebenarnya hanya ada dalam ketentuan undang-undang. Badan Pemeriksa Keuangan vs Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
630
Berkenaan dengan lembaga BPK, ada permasalahan yang timbul terutama dalam masalah pemeriksaan keuangan negara, hal mana dikarenakan adanya tumpang tindih mengenai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara tersebut. Dalam pada itu, dapat dilihat kemudian dari fungsi yang memang dimiliki antara BPK dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Bahkan, pada masa Orde Baru BPKP memiliki struktur organisasi yang jauh lebih besar dari BPK. BPKP mempunyai struktur organisasi yang menjangkau ke seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kedudukan BPKP dilihat dari fungsinya adalah lembaga internal auditor atas kegiatan pemerintahan dan pembangunan, tetapi terhadap pemerintahan yang diperiksa, sekaligus merupakan lembaga eksternal auditor. Namun setelah adanya Perubahan UUD 1945 dnyatakan dengan tegas dalam ketentuan 23E ayat (1) dinyatakan Untuk memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri(kursif penulis) Pernyataan dalam pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu lembaga yang eksternal auditor, yang nantinya akan mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, maka BPKP dengan sendirinya harus dilikuidasi, karena tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Hal ini juga untuk saling menghindari tumpang tindih mengenai tugas antara BPK dengan BPKP (asshiddiqie,2003). D. Amandemen Keempat Terjadi Pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 Agustus 2002. Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat; b) penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, Perubahan tersebut diputuskan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
631
dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.; c) pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A; d) penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara; e) pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tata Cara Pengambilan Keputusan Oleh MPR Dalam Melakukan Perubahan Terhadap UUD 1945. Perubahan yang dilakukan oleh MPR masih menyisakan suatu pertanyaan yang besar, yaitu apakah amandemen yang telah dilakukan oleh MPR sudah dilandasi dengan nilai-nilai luhur yang memang dimiliki bangsa Indonesia? Konstitusi sebagai suatu kesepakatan luhur, tentu berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya merupakan suatu kesepakatan luhur. Namun, dalam sejarahnya Perubahan UUD 1945 ternyata adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, merupakan suatu pasal yang kemudian dilahirkan dari adanya pemungutan suara, yaitu dengan menggunakan suara terbanyak (voting) oleh anggota MPR. Dengan adanya pemungutan suara tersebut, tentu dalam kenyataannya sekaligus telah membantah pernyataan MPR sendiri dalam bukunya sebagaimana dimaksud di atas. Pernyataannya MPR dalam bukunya, yaitu sebagai berikut. Suasana pada waktu itu sungguh-sungguh diliputi oleh kehendak dan tuntutan bersama berbagai komponen bangsa untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai komponen bangsa yang berasal dari aspirasi dan paham politik, ras, agama, suku, dan golongan yang beragam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
632
itu bersatu padu untuk secara bersama-sama dan konstitusional melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kehendak kolektif bangsa agar dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik. Suasana yang dibangun secara sistematis dan penuh kesadaran tersebut, baik di kalangan masyarakat, pemerintah, kekuatan sosial politik, termasuk partai-partai politik sangat mendukung berkembangnya komitmen, kesepahaman, persaudaraan, dan toleransi antar fraksi MPR. Suasana itu sangat memudahkan dan memperlancar tercapainya kesepakatan antarfraksi MPR dalam pembahasan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kuatnya komitmen, kesepahaman, persaudaraan, dan toleransi antarfraksi MPR itu terlihat dari kebersamaan fraksi-fraksi MPR dalam pembahasan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam forum rapat-rapat Panitia Ad Hoc, rapat-rapat Badan Pekerja MPR maupun dalam sidang-sidang MPR. Pada forum rapat-rapat Panitia Ad Hoc dan Badan Pekerja MPR itu, perbedaan pendapat antar fraksi MPR diberi ruang. Hal itu terlihat dari adanya beberapa rumusan alternatif materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disampaikan ke tingkat pembicaraan berikutnya, yakni pada sidang-sidang MPR. Begitu pula dalam sidangsidang MPR, pengambilan putusan terhadap materi rancangan perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap lebih mengedepankan kebersamaan. Hal itu terlihat dari pengambilan putusan terhadap materi rancangan perubahan dilakukan secara aklamasi. Terhadap materi rancangan perubahan yang belum disepakati oleh semua fraksi dalam sidang MPR, diputuskan untuk dibahas kembali pada forum rapat Panitia Ad Hoc I dan Badan Pekerja MPR untuk selanjutnya diajukan kembali pada sidang MPR berikutnya. Namun, tampaknya terkait dengan materi perubahan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, dapat dikecualikan dari pernyataan tersebut di atas. Dikarenakan tampaknya semangat kebersamaan sebagaimana yang kemudian dinyatakan di atas, tidaklah tampak terlihat dengan jelas dalam menyelesaikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Terbukti dengan adanya pemungutan suara terbanyak (voting) dari anggota MPR, untuk memutuskan terkait dengan pasal tersebut. Dalam kenyatannya ada dua pilihan terkait dengan ketentuan dalam mekanisme pengisian keanggotaan MPR. Maka, berdasarkan buku Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 tersebut penulis berkesimpulan bahwa MPR memonopoli semua kekuasaan yang ada dalam melakukan perubahan, dengan melimpahkan kekuasaan jauh lebih besar kepada DPR sebagai lembaga politik, untuk
I Gusti Ngurah Santika, SPd
633
kemudian menumpuk semua kekuasaan kepada lembaga politik tersebut, tanpa ada pilihan lainnya yang berarti. Materi yang diketahui menjadi pilihan politik pada saat itu, yaitu sebagai berikut. Alternatif 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang (kursif penulis). Alternatif 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang (kursif penulis). Pada pemungutan suara tersebut (voting), mayoritas anggota MPR yang berkenan untuk memilih alternatif 2, yaitu sebanyak 475 anggota MPR, sedangkan yang memilih alternatif 1 dipilih 122 anggota MPR, dan 3 anggota MPR memilih abstain. Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Yang mengalami Kekosongan Secara Bersamaan. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yang ditentukan mengatur pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang kosong, jika seandainya terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Maka yang berhak untuk menggantinya (pelaksana tugas kepresidenan) sementara waktu (tidak lewat dari 30), yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan (triumvirat) secara bersama-sama. Yang menjadi masalah ke depannya adalah apakah ketiga menteri tersebut, yang dalam kesehariannya merupakan menteri junior, namun dinyatakan dalam konstitusi bahwa mereka lebih berhak menggantikan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang kosong secara bersamaan tersebut, bagaimana dengan Menteri Koordinator yang notabene merupakan menteri senior daripada ketiga menteri tersebut sebagaimana biasanya? Oleh karena itu, penulis memberikan sedikit catatan terkait dengan masalah ini, yaitu adanya kesadaran akan kepatuhan terhadap ketentuan ini, dengan menjalankan menaati semua ketentuan yang ada dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Hal mana walaupun dalam kesehariannya ketiga menteri tersebut merupakan bawahan dari menteri-menteri koordinator, namun karena adanya keadaan luar biasa, yang memberikan syarat-syarat konstitusional yang telah dipenuhi dalam UUD 1945, maka tentu semuanya harus
I Gusti Ngurah Santika, SPd
634
mematuhinya, sebagai wujud daripada kesadaran akan keadaan yang harus cepat ditanggapi, karena adanya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Dengan demikian, dapat dikatakan dalam keadaan tertentu, ketiga menteri tersebut mendapat kedudukan yang spesial dalam ketatanegaraan Indonesia, berhubung dengan adanya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan pada saat itu, jadi semuanya harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang ada dalam UUD 1945, walaupun secara teori mungkin saja kurang memuaskan akal, tetapi apa yang ada sekarang itulah yang berlaku. Namun, seperti apa yang dikatakan penulis di atas, tentunya dalam praktek nanti seandainya saja benar-benar terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, maka secara praktek akan terjadi kesulitan dalam menjalankan amanat UUD 1945. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, tidak saja dengan menteri koordinator yang berada di atasnya terjadi pertentangan, namun dapat saja di antara ketiga menteri yang menjalankan tugas kepresidenan tersebut, akan bersengketa dengan sesama menteri yang diberi tugas menggantikan posisi sebagai Pejabat Presiden dan Wakil Presiden, karena kurang jelasnya kewenangan masing-masing. Dan jika masalah tersebut sampai terjadi, maka dapatlah kemudian dikatakan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan persengketaan kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Setelah itu, dengan adanya kekosongan jabatan Presiden dan Presiden secara bersamaan, yang kemudian secara otomatis diganti oleh ketiga menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, selambatlambatnya dalam waktu tiga puluh hari setelah itu, MPR harus bersidang untuk selanjutnya memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang diusulkan oleh partai politik, yang partai politik pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Dalam hal ini logikanya, ada dua partai politik pemilu sebelumnya disertai dengan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari kedua partai politik tersebut, yaitu partai politik pemenang pertama dan partai politik pemenang kedua dalam pemilu sebelumnya, kemudian mereka mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ke MPR untuk selanjutnya dipilih. Pertanyaannya adalah apakah partai politik yang sebenarnya merupakan pemenang kedua dalam pemilu sebelumnya, bersediakah bagi mereka untuk kemudian mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ke MPR untuk selanjutnya dipilih. Dalam hal ini dikarenakan kedudukannya hanyalah sebagai partai politik pemenang kedua dalam pemilu sebelumnya, yang sudah dapat dipastikan memiliki
I Gusti Ngurah Santika, SPd
635
jumlah kursi lebih kecil di MPR. Sehingga tentunya kecil kemungkinan bagi partai politik tersebut untuk dapat memenangkan kursi Presiden dan Wakil presiden, jika dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak (voting). Jika memang begitu, maka tidak mungkinlah partai politik yang sudah jelas-jelas sebagai pemenang kedua dalam pemilu sebelumnya, mau bersaing untuk memperebutkan kursi kepresidenan dengan partai politik lainnya, sedangkan partai politik tersebut yang dalam hal ini hanya memiliki dukungan kedua di MPR. Selain itu, ternyata tidak konsistennya MPR dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, hal mana berkenaan dengan tugasnya dalam pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan seperti di atas. Seharusnya dalam pengisian jabatan tersebut dapat dilakukan jika sisa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden kurang dari 1 satu tahun, maka tidak akan ada masalah bila MPR yang memilih calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti. Yang bermasalah adalah jika masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh MPR adalah lebih dari satu tahun maka, lebih baik pemilihannya diserahkan kembali kepada rakyat, untuk dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. Dikarenakan hal ini akan berimplikasi kepada pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden terpilih! Dapat saja Presiden dan Wakil Presiden tersebut diberhentikan oleh MPR secara langsung, dikarenakan menurut MPR Presiden dan Wakil Presiden sendiri telah melanggar hukum, tanpa menunggu keputusan dari MK. Dkarenakan MPR sendiri yang mengangkat mereka, tentu saja jika masalah tersebut sampai terjadi akan menimbulkan krisis ketatanegaraan yang berkepanjangan, berkaitan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) ,6A,7A,7B, 8 dan Pasal 24C UUD 1945. Bila hal tersebut terjadi, maka UUD 1945, sebenarnya sudah menentukan mekanismenya, agar nantinya tidak terjadi krisis ketatanegaraan, yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, berkaitan dengan kewenangan MK untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Nasib Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia. Lebih lanjut tentang masalah MPR yang muncul setelah Perubahan UUD 1945 berkaitan dengan kelembagaan MPR, semula MPR dirancang menjadi genus dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang nantinya akan terdiri dari dua kamar. Kamar pertama adalah DPR dan yang kedua adalah DPD. Hal ini seperti yang terdapat dalam konstitusi Amerika Serikat yang di dalamnya menentukan semua kekuasaan legislatif ada di Kongres
I Gusti Ngurah Santika, SPd
636
yang terdiri atas The House of Representative and senate demikian pula dalam konstitusi Kerajaan Belanda dikatakan bahwa kekuasaan legislatif barada di Staten Generaal yang terdiri atas Earste Kameren Tweede Kamer (Asshiddiqie,2003;14) Salah satu Konsekuensi gagasan dua kamar (terdiri dari DPR dan DPD), perlu nama bagi badan perwakilan yang mencerminkan dua unsur perwakilan tersebut, seperti Congress sebagai nama badan perwakilan yang terdiri dari Senate dan House of Representatives. Nama yang ditegaskan untuk badan perwakilan dua kamar di Indonesia adalah tetap menggunakan MPR. Sebagai konsekuensi penggunaan nama MPR sebagai nama sistem dua kamar, MPR tidak lagi menjadi suatu lingkungan jabatan (lingkungan kerja tetap tersendiri) yang memiliki lingkungan wewenang sendiri. Wewenang MPR (baru) melekat pada wewenang DPR dan DPD atau seperti UUD Amerika Serikat dan lainlain negara dengan sistem dua kamar, yang ditentukan adalah wewenang Conggress, Parliament, Staten Generaal yang pelaksanaannya dilakukan oleh kamar-kamar perwakilannya. Namun demikian, setelah perubahan keempat UUD 1945, keberadaan MPR yang selama ini disebut sebagai lembaga tertinggi negara itu memang telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, akan tetapi tetap ada sehingga sistem yang kita anut tidak dapat disebut sistem bikameral ataupun satu kamar, melainkan sistem tiga kamar (tricameralisme). Dibanyak negara, dua kamar parlemen dalam sistem bikameral itu terdiri dari Majelis Rendah (Lower House) dan Majelis Tinggi (Upper House). Sistem dua Kamar di Amerika Serikat merupakan hasil kompromi antara negara bagian yang berpenduduk banyak dengan yang berpenduduk sedikit. Perubahan susunan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, seolah mengarah pada pembentukan sistem dua kamar (Bicameral). Akan tetapi, dari susunan yang menyebutkan terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD tidak tergambar konsep dua kamar. Dalam susunan dua kamar, bukan anggota yang menjadi unsur, tetapi badan yaitu DPR dan DPD. Contohnya, Conggress Amerika Serika yang terdiri dari House of Representative dan Senate. Kalau anggota yang menjadi unsur, MPR adalah badan yang berdiri sendiri diluar DPR dan DPD (Manan dalam Huda,2011). Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan baru dalam UUD 1945, tidak tampak perwujudan gagasan sistem dua kamar, kalau dalam UUD asli hanya ada dua badan perwakilan tingkat pusat yang terpisah, sekarang justru menjadi tiga badan perwakilan. Pertama, walaupun ada perubahan, MPR tetap merupakan lingkungan jabatan sendiri. MPR memiliki wewenang sendiri (original) di luar wewenang DPR dan DPD. Kedua, sepintas lalu DPD merupakan lingkungan jabatan yang mandiri, dan memiliki lingkungan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
637
wewenang sendiri. Ketiga, DPD bukan badan legisaltif penuh. DPD hanya berwenang mengajukan dan membahas rancangan undang-undang dibidang tertentu yang disebut secara enumerative dalam UUD. Terhadap hal-hal lain, pembentukan undang-undang hanya ada pada DPR dan Pemerintah. Dengan demikian, rumusan baru UUD tidak mencerminkan gagasan mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan seluruh praktik dan pengeloalaan negara. Sesuatu yang sangat ganjil ditinjau dari konsep dua kamar. Karena itu, keberadaan DPD di samping DPR tidak dapat disebut sebagai bikameralisme dalam arti yang lazim. Selama ini, dipahami bahwa kedudukan kedua kamar itu di bidang legislatif sama kuat, maka sifat bikameralismenya disebut strong bicameralism tetapi jika kedua kamar tidak sama kuat maka disebut soft bicameralism, akan tetapi, dalam pengaturan UUD 1945 pasca Perubahan Keempat, bukan saja bahwa struktur yang dianut tidak dapat disebut sebagai strong bicameralism yang kedudukannya sama kuatnya, tetapi bahkan juga tidak dapat disebut sebagai soft bicameralism sekalipun. Dengan kata lain, DPD hanya memberi masukan, sedangkan yang memutuskan adalah DPR, sehingga DPD ini lebih tepat disebut sebagai Dewan Pertimbangan DPR, karena kedudukannya hanya memberikan pertimbangan kepada DPR. Ironisnya, mekanisme pengisian jabatan keanggotaan DPD, jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan mekanisme pengisian keanggotaan DPR. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu (Pasal 22C ayat (1) UUD 1945), anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR (Pasal 22C ayat (2) UUD 1945). Bahkan, di seluruh dunia dapat dikatakan hanya DPD lah yang merupakan perwakilan daerah yang mendapatkan legitimasi yang begitu tinggi, namun dengan kewenangan yang sangat terbatas. Keterbatasan itu memberi makna, gagasan menciptakan sistem dua kamar untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan distribusi kekuasaan menjadi suatu yang utopis (Mawardi,2008;76). Bahkan, menurut pendapat Subekti (2008;318) bagi Fraksi PDIP pembentukan DPD yang sejajar dengan DPR dikhawatirkan akan merusak NKRI karena apabila DPD kuat akan berpotensi memunculkan negara federal dan apabila kuat, akan semakin mempersulit pengendalian kepala daerah. Selain itu, berkaitan dengan jumlah anggota DPD yang tidak boleh lebih dari sepertiga anggota DPR, sementara putusan MPR diambil dengan suara terbanyak, sehingga DPD tidak bisa menjadi penyeimbang dari peran-peran DPR. Senada dengan pendapat di atas, maka Radjab (2007;37) menyatakan bahwa dibangun pula satu argumen jika parlemen di masa depan dijadikan bersifat bicameralism maka kita mendorong struktur organisasi kenegaraan kita berkembang ke arah federalisme, karena itu, terdapat usaha
I Gusti Ngurah Santika, SPd
638
keras untuk menolak cetak biru sistem bicameralisme dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Kritik berikutnya yang dapat dikemukakan menurut Winardi (2008;54-55) terkait dengan rumusan dalam ketentuan Pasal 7C UUD 1945 hanya memberikan jaminan bahwa hanya DPR yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden sehingga DPD bisa dikatakan Presiden berhak untuk membubarkannya, karena tidak ada jaminan yang tegas dan eksplisit dalam UUD. Hal ini bisa saja terjadi, misalkan Presiden terancam di impeachment oleh MPR walaupun setelah adanya keputusan MK, dengan dimulai inisiatif dari DPR. Agar dalam mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7B UUD 1945 tersebut tidak tercapai, maka Presiden dapat saja mencoba untuk membubarkan DPD. Namun, jika saja masalah tersebut terjadi, maka sudah ada MK yang bertugas untuk memutuskan. Karena masalah ini menurut penulis merupakan persengketaan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Bahkan ada yang menyatakan bahwa DPD tidak dapat dibubarkan, dikarenakan DPD sebagai lembaga perwakilan termasuk bagian daripada MPR, sehingga tentunya Presiden tidak dapat membubarkannya sekehendak hati. Namun, menurut Mahmud MD (2010) menyatakan tentang fungsi dari DPD bahwa dengan fungsi dan wewenang yang seperti itu maka sebenarnya DPD dapat dikatakan tidak mempunyai fungsi ketatanegaraan yang berarti. Peran-perannya yang sering dilakukan untuk menyampaikan aspirasi rakyat daerah terhadap pusat sebenarnya dapat dilakukan oleh Ormas dan LSM atau oleh media massa. DPD hanya penting kalau terjadi sesuatu yang akan terjadi dan sifatnya insidental berdasarkan UUD 1945, yakni terjadi perubahan atas UUD dan terjadinya impeachment terhadap Presiden/Wakil yang prosesnya sampai ke MPR. Dengan demikian, solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan semakin memperpendek jarak yang menyebabkan sistem bicameralisme dalam UUD 1945 semakin jauh dari harapan, yaitu dengan memaksimalkan tugas-tugas DPD dalam bidangnya, sehingga konsep bicameralisme semakin dekat, ditambah lagi dengan menyatukan perangkat penunjang kelembagaan antara DPR dan DPD serta jabatan ketua dan wakil ketua MPR dirangkap saja, seperti pada masa Orde Baru. Sehingga diharapkan kelemahankelemahan yang dimiliki oleh UUD 1945, terkait dengan sistem perwakilan yang dianut Indonesia bisa di atasi, semua ini dapat diakomodasi dalam undang-undang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
639
Status Penjelasan UUD 1945 Pasca Amandemen. Terkait dengan sistem ketatanegaraan seperti sekarang ini, dalam kenyataannya masih banyak yang belum mengetahui apalagi memahami secara komperhensif, baik mengenai makna perubahan UUD 1945, misalnya terkait dengan status Penjelasan UUD 1945, terutama setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945, periode 1999-2002. Banyak yang menyatakan Penjelasan UUD 1945 masih berlaku, terutama setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, hal ini dapat ditemui kemudian baik dalam buku-buku, maupun di forum-forum ilmiah. Ada yang menyatakan Penjelasan itu masih dianggap berlaku karena merupakan lampiran resmi dari UUD 1945 yang asli. Sedangkan dokumen UUD yang sekarang terdiri lima dokumen yakni UUD 1945 yang asli (yang kemudian dilampiri addendum), Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat. Dikatakan bahwa karena Penjelasan masih menempel di naskah yang asli, maka Penjelasan itu masih berlaku (Mahmud MD,2010;30). Namun, jika kemudian ditinjau secara politis terlebih dahulu ternyata dalam salah satu kesepakatannya, yang terdiri dari lima prinsip dasar yang sebelumnya menjadi kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yang menyangkut masalah penjelasan, yaitu meniadakan Penjelasan UUD 1945 dan memasukan hal-hal normatif dalam Penjelasan ke dalam pasalpasal UUD (Chaidir,2007;129). Hal tersebut jelas merupakan kesepakatan politik yang dipegang oleh MPR, dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yang selanjutnya direalisasikannya kembali dengan memasukan isi Penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Indonesia yang menganut negara hukum, kemudian dimasukan ke dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan Negara Indonesia ialah negara hukum. Dan bahkan masih banyak ketentuan lain dari Penjelasan UUD 1945, yang kemudian dimasukan ke dalam Pasal-Pasal UUD 1945 setelah perubahan. Bahkan secara historis Asshiddiqi (2006;125-126) menyatakan penjelasan UUD 1945 dibuat oleh Soepomo ,Penjelasan tentang UUD 1945 itu diumumkan resmi dalam Berita Repoeblik Tahun 1946 dan kemudian dijadikan bagian lampiran tak terpisahkan dengan naskah UUD 1945 oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Hal mana dengan jelas dapat diketahui, jika kita membaca Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, yang merupakan proses persidangan dalam pembentukan UUD 1945, di mana yang menjadi pembahasannya hanyalah Pembukaan (preambule) dan Batang Tubuh. Jadi, Penjelasan UUD 1945 sebelum di hapus, ternyata bukanlah hasil karya dari BPUPKI dan PPKI, melainkan buatan Soepomo yang disarikan dari sidang-sidang tersebut. Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat Soemantri (1992;39) yang menyatakan penjelasan dimaksud tidak pernah dibicarakan baik
I Gusti Ngurah Santika, SPd
640
dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (Indonesia) maupun dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dalam kenyataannya banyak isinya yang tidak berkesesuaian lagi antara pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 dengan isi Penjelasan UUD 1945. Bahkan, banyak ketentuan dalam Penjelasan UUD 1945, yang tidak sesuai dengan negara konstitusional, di mana konsep utamanya memberikan jaminan hak asasi manusia, di samping mampu membatasi kekuasaan penguasa. Seperti apa yang kemudian dikemukakan oleh Asshiddiqie (2005;86) bahwa sebagian materi Penjelasan sama sekali merupakan soal baru yang tidak terdapat dalam pasal-pasal UUD, seperti misalnya istilah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, ataupun istilah Mandataris MPR yang dalam penerapannya menimbulkan masalah karena justru memperkuat kecendrungan terjadinya penumpukan kekuasaan disatu orang yang kebetulan menduduki jabatan Presiden. Status penjelasan UUD yang sebenarnya sangat penting dalam rangka penafsiran secara historis atau penafsiran otentik terhadap UUD 1945, menimbulkan kaidah hukum baru yang diperlakukan sederajat dengan materi UUD. Hal ini terkait dengan kesepakatan tentang peniadaan Penjelasan UUD 1945 disebabkan pandangan dari MPR bahwa penjelasan jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesulitan statusnya dari sisi sumber hukum dan tata urutan (hierarkhi) peraturan perundangundangan (Atmadja,2006;74). Sedangkan, terkait dengan kebiasaan adanya suatu UUD yang memiliki sebuah penjelasan, maka Asshiddiqie dan Manan (2006;10) menyatakan bahwa: tidak ada kelaziman UUD memiliki Penjelasan yang resmi. apalagi memuat, baik secara hukum atau kenyataan, Penjelasan diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti UUD (Batang Tubuh). Bahkan, jika dilihat kembali, terutama secara yuridis setelah Perubahan UUD 1945 yang keempat, maka dapat ditemui dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan, yang menegaskan secara implisit, dengan menentukan status dari kedudukan Penjelasan UUD 1945, yang di dalamnya menyatakan Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Dengan demikian, jelaslah bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2002, status Penjelasan UUD 1945 yang selama ini dijadikan lampiran tak terpisahkan dari naskah UUD 1945, tidak lagi diakui sebagai bagian dari naskah UUD. Jikapun, isi Penjelasan itu dibandingkan dengan isi UUD 1945 setelah empat kali berubah, jelas satu sama lain sudah tidak berkesuaian, karena pokok pikiran yang terkandung di dalam keempat naskah perubahan itu sama sekali berbeda dari apa yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut (Asshiddiqie,2004;50). Jadi dengan sendirinya, penjelasan UUD 1945 dianggap tidak ada lagi. Dengan adanya ketentuan Pasal II aturan tambahan itu, orang tidak mungkin dapat lagi menyebutkan bahwa UUD 1945 dan perubahan-
I Gusti Ngurah Santika, SPd
641
perubahannya terdiri dari Pembukaan, Batang Tubung, dan Penjelasan, seperti yang sebelumnya biasa dinyatakan demikian (Syahuri,2004;159). Bahkan, setelah perubahan pertama dan kedua terhadap pasal-pasal UUD 1945, menyebabkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945, sudah berubah sangat drastis. Sehingga menyebabkan pula perbedaan antara pokok pikiran yang baru dalam UUD 1945 pasca perubahan, dengan Penjelasan UUD 1945 yang menganut paradigma yang lama. Oleh karena itu, setelah perubahan UUD 1945 yang terakhir pada tahun 2002, Penjelasan UUD 1945 telah dihapus, namun demikian, beberapa hal pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam penjelasan yang telah dihapus tersebut, masih ada beberapa materi yang masih bisa dikatakan relevan. Dikarenakan masih sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia sekarang, sehingga masih dapat digunakan sebagai landasan teori dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dari berbagai pendapat para ahli yang telah penulis sampaikan di atas, khususnya berkaitan dengan tidak lazimnya suatu UUD memiliki penjelasan, ternyata ada seorang sarjana yang memberikan pendapat yang berbeda yaitu Joeniarto (1996;19) yang menyatakan alasan tiada lazim, bahwa sesuatu Undang-Undang Dasar disertai dengan penjelasan, andai kata benar demikian, maka kita tidak perlu menirunya. Di dalam prakteknya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar kadang-kadang belum cukup memberikan kejelasan, maka dengan adanya Penjelasan sungguh-sungguh besar sekali manfaatnya. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa suatu UUD yang telah ditetapkan oleh suatu bangsa, merupakan sebuah kesepakatan politik. Tentunya suatu kesepakatan politik dari suatu negara dengan negara lain akan berbeda, apalagi berkaitan dengan isi daripada UUD, yang sebenarnya merupakan hasil dari kesepakatan politik tersebut. Tidak lain disebabkan, karena UUD merupakan pedoman dalam rangka menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ditelusuri kembali dari sejarahnya, memang akan tampak terlihat jelas bahwa Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus, bukanlah merupakan hasil karya dari BPUPKI dan PPKI. Dikarenakan pada saat sidang-sidang di kedua badan tersebut, yang ketika itu dibahas hanya berkaitan dengan Pembukaan dan Batang Tubuh (Pasal-Pasal), yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, terkait dengan hal tersebut dapatlah diakui kebenarannya. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan perubahan-perubahan seperti di atas, kemudian diumumkan dengan resmi dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946 (Syahuri,2004;118). Kemudian keberadaan Penjelasan di perkuat lagi dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dapat dilihat dari perbedaan antara Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah Dekrit Presiden. Karena eksistensi Penjelasan dapat kita temui
I Gusti Ngurah Santika, SPd
642
secara yuridis, hal mana dinyatakan Penjelasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945, ditambah lagi dengan dimasukannya dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 75. Sehingga dengan demikian, penulis tidak menyangsikan lagi keabsahan dari Penjelasan UUD 1945 tersebut, walaupun banyak kontroversi yang mengiringi perjalanannya. Walaupun menurut Mahmud MD (2010;44) tindakan memasukan UUD 1945 disertai dengan Penjelasannya tersebut merupakan tindakan politis, bukan imperatif yuridis, untuk memastikan pandangan pemerintah atau Presiden bahwa naskah-naskah itulah yang berpedomani oleh pemerintah berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Fungsi Pasal 1 Peraturan Peralihan UUD 1945. Selain berbagai permasalahan ketatanegaraan yang penulis temukan di atas, ada satu lagi permasalahan penting yang dipandang perlu untuk selanjutnya dibahas. Berkenaan dengan Peraturan Peralihan dalam Pasal I UUD 1945, yang menyatakan bahwa: Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dari kalimat tersebut dapat dikatakan sedikit memiliki arti membahayakan, dikarenakan hampir bisa kemudian ditafsirkan bahwa segala peraturan perundangundangan yang ada tetap berlaku, meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini, apabila belum diadakan peraturan perundang-undangan baru, yang bertugas menggantikan peraturan perundang-undang lama yang bertentangan tersebut. Jadi dengan adanya ketentuan Pasal 1 Peraturan Peralihan tersebut, maka semua hukum yang sudah berlaku, baik sesudah maupun sebelum UUD 1945 diamandemen, tetap berlaku sampai diaturnya peraturan tersebut dengan peraturan yang baru. Bahkan peraturan-peraturan hukum pada zaman penjajahan masih banyak yang berlaku hingga saat ini, seperti Wetboek Van Strafreht (KUHP), Wetboek Van Kophandel (KUHD), Bugerlijk Recht, Privaat recht, bugerlijk wetboek (KUH Perdata). Berlakunya peraturan hukum tersebut sebenarnya berdasarkan asas konkordansi artinya bahwa hukum yang berlaku di negeri jajahan (Hindia Belanda) sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda (Salim,2009;12). Dengan demikian, Pradjodikoro (2008;8) berpendapat bahwa ketentuan yang terakhir ini sering dilupakan oleh mereka yang cenderung menganggap semua peraturan dari zaman penjajahan Belanda yang tidak secara tegas dicabut dan diganti, tetap berlaku tanpa kekecualian. Kemudian, yang menjadi latas belakang masih berlakunya peraturan zaman kolonial tersebut di atas, dikarenakan revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945, tidak secara mutlak menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman kolonial. Kalau ada
I Gusti Ngurah Santika, SPd
643
yang dihapus, maka belum ada hukum penggantinya, terutama disebabkan karena tujuan utama dari revolusi fisik adalah mencapai dan mempertahankan kemerdekaan (Soekanto,2009;185). Padahal di antara peraturan-peraturan itu ada beberapa yang jelas hanya layak dalam hubungan-hubungan kolonial. Banyak norma,yang dikembangkan untuk memfasilitasi pemerintah kolonial dalam mempertahankan kekuasaannya (Dwiyanto,2005;28). Walaupun menurut keyakinan Hasyim (2009;10) yang menyatakan dengan adanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka segala peraturan yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang bertentangan dengannya adalah batal demi hukum. Maksud lahirnya ketentuan Pasal II Peraturan Peralihan seperti tersebut di atas, juga diterangkan kembali oleh Kaho (1985;31) yang menyatakan bahwa jika suatu undangundang memberi suatu pengaturan pada suatu obyek yang juga diatur oleh undang-undang yang lama dengan sendirinya undang-undang yang lama itu kehilangan kekuatannya. Ketentuan Pasal II Peraturan Peralihan merupakan salah satu syarat untuk berakhirnya suatu undang-undang. Selain itu juga, terdapat syarat lain untuk berakhirnya masa berlakunya undang-undang, seperti jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undangundang itu sudah lampau, keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi, undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi (Kansil dan Christine,2002;20). Berkaitan dengan ketentuan undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama, maka ini merupakan suatu asas yang biasanya berlaku dalam hukum. Dengan demikian, hal tersebut sama dengan undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (Soekanto,2010;12) (lex posteriori derogate lex priori). Oleh karena itu, penulis berpendapat seharusnya memang aturan peralihan ini adalah untuk mencegah kekosongan hukum, dalam hal ini pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Harsono (2008;14) berkaitan dengan ketentuan peralihan merupakan asas umum dalam perundang-undangan bahwa jika terjadi perubahan hukum, peraturan-peraturan yang lama tidak berlaku lagi dalam rezim hukum yang baru. Tetapi biasanya hukum yang baru itu belum seluruhnya lengkap ketika mulai berlaku. Maka untuk mencegah apa yang dinamakan kekosongan hukum biasanya hukum yang baru tersebut, selama belum ada peraturan yang menggantinya, masih terus memberlakukan peraturan-peraturan yang lama tanpa atau disertai pembatasan-pembatasan tertentu. Terus memberlakukan peraturanperaturan yang lama dalam rezim hukum yang baru tersebut dilakukan dengan mengadakan apa yang disebut peraturanperaturan peralihan (peraturan-peraturan transitoir). Dalam
I Gusti Ngurah Santika, SPd
644
hal ini tentunya tidak semua peraturan lama yang masih belum ada penggantinya, harus juga dengan meneruskan memberlakukan undang-undang tersebut, padahal isinya jelasjelas bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, dengan berlakunya aturan peralihan di atas, seharusnya disertai pula dengan pembatasan terhadap suatu undang-undang yang benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, harusnya tidak perlu untuk diberlakukan, meskipun dalam kenyataannya belum ada undang-undang baru, yang nantinya akan menggantikan undang-undang yang bertentangan tersebut. Hanya saja tentu penerapannya di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara murni dan konsisten sebagaimana maksud awal kelahiran daripada norma tersebut, melainkan penafsirannya menyesuaikan dengan kehidupan bangsa yang telah merdeka serta sebagai bangsa beradab apalagi sebagai negara yang mendasarkan diri pada Pancasila sebagai dasar negara. Mertokusumo dalam Salim (2009;13) menyatakan tata hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi sebagai tata hukum nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sekarang ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, peraturan prundang-undangan serta dibutuhkan. pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Joeniarto (1996;15) bahwa untuk menjaga agar jangan sampai ada kekosongan hukum maka peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang ada dan masih berlaku, sepanjang hal itu masih diperlukan serta pula tidak bertentangan dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, tentu saja masih boleh diteruskan berlakunya sampai diganti, diubah, dicabut atau dilemahkan dengan peraturan atau ketetapan yang baru. Hal ini lebih-lebih ternyata dalam jaman peralihan yang dialami oleh negara-negara baru bekas jajahan, dalam mana peraturan-peraturan hukum dari tata hukum yang bersifat kolonial, masih dapat berlaku asal saja tidak bertentangan dengan tata hukum baru dari negara yang sudah merdeka (Prodjodikoro,1981;93). Peraturan peralihan ini, merupakan aturan yang berfungsi untuk melanjutkan peraturan yang dulunya berlaku, tetapi sekaligus digunakan sebagai suatu filter, yang tentunya menyaring segala peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun, seharusnya dicantumkan secara tegas, apabila dikemudian hari ada suatu peraturan perundang-undangan setelah adanya Perubahan UUD 1945, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut sebenarnya sudah pernah dilakukan setelah kemerdekaan, yaitu untuk mengantisipasi peraturan perundangundangan yang benar-benar bertentangan dengan alam kemerdekaan Indonesia. UndangUndang tersebut adalah UU No. 1 Tahun 1946, tanggal 26 Februari 1946, dalam peraturan tersebut mengandung dua pasal berikut.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
645
Pasal I:Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut (kursif penulis). Pasal 2:Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut siapakah yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang ada pada zaman kolonial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Menurut hemat penulis, dengan adanya ketentuan tersebut dapat kemudian dikatakan telah memberikan kewenangan secara tidak langsung, khususnya kepada hakim yang menerima perkara dalam peradilan, untuk selanjutnya memberikan penilaian atas peraturan perundang-undangan, apakah benar-benar bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti bukan pengujian peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945 pasca amandemen, yang mana untuk sekarang ini hakim konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang berlaku. Pengujian yang dilakukan sebagaimana dimaksudkan penulis pada waktu itu, yaitu jika dirasa memang peraturan tersebut merupakan suatu peraturan yang terlihat jelas-jelas bertentangan dengan kehidupan alam Indonesia merdeka. Maka peraturan tersebut, tentunya dianggap tidak ada ataupun penafsiran akan berbeda dengan maksud awal daripada peraturan tersebut dilahirkan, sehingga menjadi sesuai dengan negara yang beradab. Sedangkan untuk sekarang, penulis rasa mengapa berkaitan dengan masalah tersebut tidak kemudian dicantumkan dalam sebuah ketentuan, seperti sebagaimana dimaksud di atas setelah perubahan UUD 1945, tepatnya dalam ketentuan Pasal I Peraturan Peralihan. Pertama, dikarenakan untuk sekarang, telah ditentukan kepada lembaga negara (MK dan MA) untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah terhadap peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Sehingga tidak setiap lembaga negara/orang kemudian dapat menafsirkan, apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak, dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Namun, sesungguhnya dengan adanya ketentuan lebih tegas yang berfungsi mengatur kewenangan untuk menyatakan, jika ada peraturan yang memang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang benar-benar dijungjung tinggi. Maka hakim perlulah diberikan sebuah kewenangan, untuk sekedar menyampingkan peraturan tersebut, yang sebenarnya jelas-jelas tidak sesuai dengan perkembangan Indonesia, yang pada dasarnya menganut paham negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Dalam pada itu, dengan penafsiran adanya hakim, sehingga ketentuan yang dulunya bertentangan dengan UUD 1945, berubah menjadi sesuai dengan
I Gusti Ngurah Santika, SPd
646
UUD 1945, di samping tentunya tidak bertentangan dengan tujuan proklamasi kemerdekaan. Dengan demikian, di zaman RI 45 Pancasila memberi isi dan batasan pada kebebasan hakim. Mengingat akan masih adanya dualisme hukum dan masih berlakunya peraturan-peraturan yang tidak lagi sesuai dengan keadaan, maka Pancasila memungkinkan hakim lebih bebas bergerak dalam menafsirkan ketentuan undang-undang. Pancasila memberikan cukup pedoman-pedoman bagi hakim untuk menggunakan ketentuanketentuan undang-undang dengan cara yang sebaik-baiknya dengan persoalan hukum yang riil dihadapi oleh hakim (Mertokusumo,2011;129)
I Gusti Ngurah Santika, SPd
647
DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU Abdy, Yuhana. 2009. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan Di Indonesia dan Masa Depan MPR RI .Edisi Revisi Bandung: Fokus Media. Abdullah, H. Rozali. 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Cet X. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. .dan Ayamsir. 2004. Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Cet II. Bogor : Ghalia. Abdussalam. H. R. 2007. Kriminologi. Cet III. Jakarta : Restu Agung. Abdurrahman dan Syahrani, Riduan.1978. Hukum Dan Peradilan. Cet I. Bandung : Alumni. Abdurrahman, Mulyono. 2009. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Cet II. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Rineka Cipta. Abidin, Wikrama Iryans. 2005. Politik Hukum Pers Indonesia. Cet I. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Adisubrata, Winarna Surya. 2003. Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi). Cet I. Semarang : Aneka Ilmu. Adji, Oemar Seno. 1978. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta : Erlangga. Adolf, Huala. 2002. Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Afandi, Wahyu. 1981. Hakim Dan Penegakan Hukum. Bandung: Alumni. Agung, Ide Anak Gede. 1995. Pernyataan Rum Van Roijen (Rum Van Roijen statemen 7 Mei 1949. Surakarta : Yayasan Pustaka Nusatama bekerjasama dengan Sebelas Maret University Press. .1995. Persetujuan Linggar Jati, Prolog dan Epilog. Yayasan Pustaka Nusatama bekerjasama dengan Sebelas Maret University Press.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
648
Ahmadi, H. Abu. 2007. Psikologi Sosial. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta. Dan. Uhbiyati, Nur. 2003. Ilmu Pendidikan. Cet II. Jakarta : Rineka Cipta. Alfian, Alfan M. 2012. Demokrasi Pilihanku; Warna-Warni Politik Kita. Cet II. Malang : In-Trans Publishing Ali, Achmad. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Yudicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Cet IV. Jakarta : Prenada Media Group. Ali, Zainuddin .H. 2010. Filsafat Hukum. Cet IV. Jakarta : Sinar Grafika. Amal, Ichasul dan Panggabean, Samsurizal. 2012. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Edisi Kedua. Yogyakarta : Tiara Wacana. Amin Rais, 1989. Politik Internasional Dewasa Ini. Cet I. Surabaya : Usaha Nasional. Amin, Zainul Itijhad. 1999. Pendidikan Kewiraan. Cet II. Jakarta : Universitas Terbuka. Andasasmita, Komar. 1983. Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia. Bandung : Alumni. Anshari, H. Endang Saifuddin. 1986. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 1959. Edisi II. Jakarta : CV Rajawali. Anshari, Tunggu dkk. 2009. Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Semarang: Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah dengan Universitas Brawijaya. Anthony, Lewis. 1984. The Supreme Court And How It Work. Terjemahan. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Anwar, M. Syafi. 1998. Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat : 75 Tahun Prof. Miriam Budiardjo. Bandung : Mizan. Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2003. Hukum Internasional; Bunga Rampai. Cet I. Bandung : PT. Alumni.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
649
Arief, Barda Nawawi. 2010. Perbandingan Hukum Pidana. Edisi Revisi. Cet VIII. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Arifin, Firmansyah dan Wardi, Juliyus. 2002. Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitus di Indonesia. Cet I. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Arsana, I Made Andi. 2007. Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis. Cet I. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. . 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. .2012. Pengantar Hukum Tata Negara. Cet IV. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. . 2010. Green constitution; Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ed II. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. .. 2009. Dalam kata pengantar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Cet VI. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. . Dan Manan, Bagir.2006. Gagasan Amandemen UUD1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung. Jakarta : Sekertaris Jenderal dan Mahkamah Konstitusi RI. . 2011. Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi dalam Memahami Hukum; Dari Konstruksi Sampai Implementasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. . 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Kelompok Gramedia. . 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
650
. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Cet. II. Jakarta : Konstitusi Press bekerjasama dengan PT Syaamil Cipta Media. . 2006. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Cet. I. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. . 2004. Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya. Jakarta : Sekertariat Mahkamah Konstitusi. . 2004.Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI. . 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: Mahkamah Konsitusi. Terhadap
. dan Syahrizal, Ahmad. 2012. Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. . Dan Safaat, M.Ali. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Cet. I. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Astawa, I Gede Pandja dan Suprin. 2009. Memahami Ilmu Negara danTeori Negara. Bandung : PT Refika Aditama. Attamimi, Hamid. S. dalam Oetojo Oesman Dan Alfian. 1992.Pancasila Sebagai Ideologi, Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara. Cet. II. Jakarta : BP -7 Pusat. Atmaja, Jiwa. 2002. Menyelamatkan Bali Pasca Otonomi Daerah dalam Otonomi Daerah Bali : Kendala dan Harapan. Cet I. Denpasar : Ikayana. Atmadja, Dewa Gede. 2012. Ilmu Negara : Sejarah, Konsep Dan Kajian Kenegaraan. Malang : Setara Press. . 2006. Hukum Konstitusi Perubahan Konstitusi Sudut Pandang Perbandingan. Denpasar : Bali Age. Atmasasmita, H.Romli. 2007. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Edisi Revisi. Bandung : Refika Aditama.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
651
Apeldoorn, Mr. L.J. Van. 2011. Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht. Terjemahan. Cet. XXXIV. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Azhary, Tahir. 2010. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini. Jakarta : Prenada Group. Azhary. 1983. Ilmu Negara ; Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg. Cet. IV. Jakarta: Ghalia Indonesia. Bachar, Djazuli. 2005. Aneka Pengalaman Kesan Dan Angan-Angan Seorang Mantan Hakim. Cet I. Yogyakarta : Liberty. Bakhtiar, Amsal. 2008. Filsafat Ilmu. Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Baldwin, James Mark. 2007. History of Psychology A Skecth and an Interpretation. Terjemahan. Yogykarta : Prismasophie. Barros, James. 1984. United Nation : Past, Present and Future.Terjemahan. Jakarta : Bumi Aksara. Basah, Sjachran. 1985. Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Aministrasi Di Indonesia.Bandung : Alumni. Berten,K. 2011. Etika. Cet. XI. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Bisri, Ilhami. 2010. Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia. Edisi I . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Brotodihardo, Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi III. Cet XVIII. Bandung : PT. Refika Aditama. Budiardjo, Mirriam. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. . 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Bungin, H.M. Burhan. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa : Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Cet I. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
652
Busroh, Daud. 2001. Ilmu Negara. Cet II. Jakarta : Bumi Aksara. .dan Busroh. 1991. Asas-asas Hukum Tata Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia. . 1994. Capita Selekta Hukum Tata Negara. Cet I. Jakarta : Rineka Cipta. .1985. Hukum Tata Negara. Cet I. Jakarta : Ghalia Indonesia. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 1999. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Edisi Maret. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP. Cassese, Antonio. 2005. Human Right in a changing world. Terjemahan. Cet II. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Chaidir, Ellydar. 2007. Hukum Dan Teori Konstitusi. Yogjakarta : Kreasi Total Media Yogyakarta. Changara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik ; Konsep, Teori dan Strategi. Edisi I. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Cutlip, Scott M dkk. 2006. Effective Public Relation. Terjemahan. Edisi IX. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Dahl, Robert A. 1985. Dilemmas Of Pluralist Democrazy. Terjemahan. Cet I. Jakarta : CV Rajawali. . 2001. On Democrazy. Terjemahan. Cet I. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. . 1992. Democrazy and its critics. Terjemahan. Cet I. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Danim, Sudarwan. 2010. Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru. Cet II. Bandung : Alfabeta. Darmodihardjo, Darji dkk. 1991. Satiaji Pancasila. Edisi Revisi. Cet X. Surabaya : Usaha Nasional. . 1984. Pancasila Suatu Orientasi Singkat. Cet XII. Jakarta : Aries Lima.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
653
Depari, Eduard dan MacAndews, Colin. 1995. Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan. Cet VI. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Dirdjosisworo, Soedjono. 2003. Pengantar Ilmu Hukum. Cet XVII. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Djahiri, Achmad Kosasih. 1978. Tentang dan Masalah Pancasila U.U.D 45 dan Hak-Hak Azasi Manusia. Bandung : Jemmars. Djamal. 1986. Pokok-Pokok Bahasan Pancasila. Edisi II. Bandung : Remadja Karya. Djamali, Abdul. 2008.Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Djokosoetono. 2006. Ilmu Negara Dihimpun oleh Harun Alrasid. Edisi Revisi. Jakarta : In - Hill Co. Djumhur dan Danasaputra, H. 1976. Sejarah Pendidikan untuk PGA 6 Tahun: SPG;KPG dan Sekolah-Sekolah/Kursus-Kursus Guru yang sederajat. Cet VI. Bandung: CV Ilmu. Dotomuljono. 1985. Kekuasaan MPR Tidak Mutlak. Cet I. Jakarta : Erlangga. Duverger, Maurice. 2010. The Studi of politics (sosiologi politik). Terjemahan. Cet 13. Jakarta : PT RajaGrafindo. Dwidjowijoto, Rian Nugroho. 2004. Komunikasi Pemerintahan: Sebuah Agenda Bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Cet I. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Echols, John M dan Shadily, Hassan. 2006. Kamus Indonesia Inggris. Edisi Ketiga. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Edstrom, Judith. 2009. Seri Manajemen Pelayanan Publik, Reformasi Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah ; Kajian Akademis. Jakarta : Departemen Dalam Negeri. Elson, R.E. 2009. The Idea Of Indonesia. Terjemahan. Cet1. Jakarta : Serambi. Erwin, Muhamad. 2009. Hukum Lingkungan Dalam Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Cet II. Bandung : Refika Aditama.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
654
. 2011. Filsafat Hukum; Refleki Kritis Terhadap Hukum. Cet I. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Fadjar, Mukthie. 2005. Tipe Negara Hukum. Malang : Banyumedia Publising. . 2010. Konstitusionalisme Demokrasi, Sebuah Diskursus tentang Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi sebagai Kado untuk Sang Penggembala. Malang : In-Trans Publishing. . 2008. Partai Politik Dalam Indonesia.Cet I. Malang : In Trans Publising. Sistem Ketatanegaraan
Fatmawati. 2010. Struktur Dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral ; Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara. Jakarta : UI Press. . 2005. Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia. Cet I. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Faturohman, Deden dan Sobari, Wawan. 2002. Pengantar Ilmu Politik. Malang : Muhammadyah Malang Press. Feith, Herbert. 2001. Dinamics of guided democracy, In Ruth T. Mc Vey. Terjemahan. Cet II. Jakarta : Sinar Harapan. Forsythe, David. 1993. Human Rights and World Politics. Terjemahan. Bandung : Angksa. Fuady, Munir. 2010. Konsep Negara Demokrasi. Bandung : Refika Aditama. .2011.Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum. Edisi I. Jakarta : Prenada Media Group. Fudyatanta, Ki. 2006. Filsafat Pendidikan Barat Dan Filsafat Pendidikan Pancasila; Wawasan Secara Sistematik. Edisi II. Yogaykarta : Amus. Fukuyama, Francis. 2005.State-Building Governance and World in the 21s Century.Terjemahan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Gautama, Sudargo. 1977. Tata Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan). Cet I. Bandung : Alumni. . 2005. Hukum Antar Tata Hukum. Cet IV. Bandung : Alumni.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
655
Gerungan. W.A. 2002. Psikologi Sosial. Cet XV. Bandung : Refika Aditama. Ghaffur, Abdul. 2009. Perbandingan Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju. Cet. I. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hadi, Hardono.1994. Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila. Cet I. Yogyakarta : Kanisius. Hadi, Nurudi. 2007. Wewenang Mahkamah Konstitusi (Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu. Cet I. Jakarta : Prestasi Pustakaraya. Hadjon, Philipus M. 1987. Lembaga-Lembaga Tertinggi Negara Menurut UndangUndang Dasar 1945 : Suatu Analisa Hukum Dan Kenegaraan. Cet I. Surabaya : PT Bina Ilmu. Hadjon, Philpus M, dkk. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Cet IX. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Halim, Abdul. 2000. Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Resfonsif. Edisi I. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Hamalik, Oemar. 2010. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta : Bumi Aksara. Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa. 2010. Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia. Cet I. Bandung : Alumni. Hamzah, Fahri. 2012. Demokrasi, Transisi, Korupsi; Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik. Cet II. Tanpa tempat : Yayasan Faham. Handayaningrat, Soewarno. 1986. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Cet IV. Jakarta : PT. Gunung Agung. Harahap, M.Yahya. 2005. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Cet III. Jakarta : Sinar Grafika. Hardiman, F. Budi. 2007. Flsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Cet II. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hardjasoemantri, Koenadi. 1986.Hukum Tata Lingkungan. Edisi II. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
656
Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia ; Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya. Edisi Revisi. Jakarta : Djambatan. . 1986. Hukum Agraria Indonesia : Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah. Cet VII. Jakarta : Djembatan. Hartono, M. Dimyati. 2009.Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Cet I. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. . 2010. Memahami Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dari Sudut Historis, Filosofis, Ideologis, dan Konsepsi Nasional. Depok : Gramata Publishing. Hartono, Sunarjati. 1982. Apakah The Rule Of Law Itu?. Cet IV. Bandung : Alumni. Hasyim, Farida. 2009. Hukum Dagang. Edisi I. Cet II. Jakarta : Sinar Grafika. Hasyim, Mustofa W. 2000. Jejak Luka Politik dan Budaya. Cet I. Yogayakarta : Lipsas Prospek. Hazairin. 1981. Tujuh Serangkai Tentang Hukum. Cet III. Jakarta: Bina Aksara. .1990. Demokrasi Pancasila. Cet VI. Jakarta : Rineka Cipta. Huda, NiMatul. 2010. Ilmu Negara. Edisi I.Jakarta : RajaGrafindo Persada. . 2011. Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Huijbers, Theo. 2011. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Cet. XVIII. Yogyakarta : Kanisius. . 2010. Filsafat Hukum. Cet XV. Yogyakarta : Kanisius. Husni, Lalu. 2007. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan. Cet III. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hutabarat, Martin, dkk. 1996. Hukum Dan Politik Indonesia, Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Hutauruk, M. 1978. Azas-Azas Ilmu Negara. Cet II. Jakarta : Erlangga.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
657
Hutington,Samuel P. 1983. Political Order in Changing societies. Terjemahan. Cet I. Jakarta : CV Rajawali. Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan I ; Jenis, Fungsi, dan Muatan. Cet XII. Yogyakarta : Kanisius. .2007. Ilmu Perundang-Undangan II ; Proses dan Teknik Pembentukannya. Cet IX. Yogyakarta : Kanisius. Islamy, M. Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Cet XIII. Jakarta : Bumi Aksara. Ismail, Taufiq. 2002. Tirani Dan Benteng. Cet I. Jakarta : Yayasan Indonesia. Isra, Saldi. 2010. Pergeseraran Fungsi Legislasi ; Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. . 2010. Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi Sebuah Kumpulan Wawancara. Cet I. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Iver, Mac. 1988. The Modern State. Terjemahan. Cet II. Jakarta : Aksara Baru. Joeniarto. R. 1982. Perkembangan Pemerintahan Lokal. Cet III. Bandung : Alumni. . 1983. Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia. Cet IV. Yogyakarta : Liberty. .1996. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Cet III. Jakarta : Bumi Aksara. Jurdi, Fajlurrahman. 2007. Komisi Yudsial ; Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim. Cet I.Yogyakarta : Kreasi Wacana. Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila. Edisi Revisi.Yogyakarta : Paradigma Yogyakarta. . 2002. Fisafat Pancasila; Pandangan Hidup Bangsa. Edisi I. Yogayakarta : Paradigma. . 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogayakarta : Paradigma.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
658
Kaho, Josef Riwu.1983. Proses dan Teknik Perundang-Undangan. Edisi I. Jakarta : Bina Aksara. Kansil, C.S.T.1985.Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah : Dilengkapi Dengan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Cet III. Jakarta : Aksara Baru. dan Cristiane Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Balai Pustaka. . 2004. Ilmu Negara Umum dan Indonesia. Jakarta :Pradnya Paramita. .2011. Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara. Jakarta : Rineka Cipta. . 2000. Ilmu Negara Untuk Perguruan Tinggi. Cet III. Jakarta : Sinar Grafika. .1986. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 . Cet VIII. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. .1985. Memilih dan Dipilih : Inti Pengetahuan Pemilihan Umum Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1985 Untuk Siswa/Mahasiswa/Umum. Cet III. Jakarta : Pradnya Paramita. . 2002. Hukum Tata Negara Republik Indonesia II. Cet II. Jakarta : Rineka Cipta. Kantaprawira, Rusadi. 1990. Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar. Cet VI. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Kirdi, Dipuyudo. 1985. Keadilan Sosial ; Seri Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila 1. Jakarta : CV Rajawali. Karim, M. Rusli. 1983. Perjalanan Partai Politik Indonesia Sebuah Potret PasangSurut. Cet I. Jakarta : CV Rajawali. Kartohadiprodjo, Sodiman. 1984. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Cet. X. Jakarta : Penerbitan bersama PT. Pembangunan dengan Ghalia Indonesia. Kartosapoetra, R.G. 1987. Sistematika Hukum Tatanegara. Cet I. Jakarta : Bina Aksara.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
659
Kelsen, Hans. 2011. General Theory of Law and State. Terjemahan. Bandung : Nusamedia. . 2010. Introduction the to Problems of Legal Theory. Terjemahan. Cet III. Bandung : Nusa Media. Kementerian Penerangan. Tt. Kembali Ke Undang-Undang Dasar1945. Jakarta : Kementerian Penerangan RI. Kencana, Inu dan Azhari. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung : Refika Aditama. Kleden, Ignas. 2004. Partai Politik dan Politik Partai dalam Pergulatan Partai Politik di Indonesia. Cet I. PT RajaGrafindo Persada. Koentjaraningrat. 2005. Pengantar Antropologi I. Cet III. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Koesoematdja, Djenal Hoesen.1983. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara 1. Cet II. Bandung : Alumni. Kranenburg. 1983. Algemene Staatleer. Terjemahan. Cet IX. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Etika Aministasi Negara. Cet VI. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Kurzwiel, Edith. 2004.The Age of Structuralism, Levi-Straus to Foucault. Terjemahan. Yogyakarta : Kreasi Wacana. Kusnardi, Moh. Dan Sarigih, Bintan R. 2008. Ilmu Negara. Edisi Revisi. Jakarta : Gaya Media Pratama. .1986. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945. Cet V. Jakarta : PT. Gramedia. Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Etty R. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung : PT. Alumni. . Dan Sidharta, B. Arief. 2000. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku I). Bandung : Alumni. . 2003. Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III. Cet I . Bandung : PT. Alumni.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
660
Latif, H. Abdul. 2009.Fungsi Mahkamah Konstitusi; Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi. Cet II. Yogyakarta : Kreasi Total Media. . dan Ali. 2010. Politik Hukum. Edisi I. Jakarta: Sinar Grafika. Learner, Daniel. 1983. The Passing of Traditional Society Modernizing the Midle East. Terjemahan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Lembaga Administrasi Negara. tt. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid I. Jakarta : CV Haji Mas Agung. Lev, S Daniel. 2013. Politik dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan. Cet. III. Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia. Lopa, Baharuddin dan Hamzah, Andi. 1991. Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi II. Jakarta : Sinar Grafika. Lubis, T. Mulya dkk. 1983. Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia 1981. Jakarta : Sinar Harapan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Lubis, M. Solly. 1980. Asas-Asas Hukum Tata Negara. Cet III. Bandung : Alumni. . 1980. Pembahasan UUD 1945. Edisi Baru. Bandung : Alumni. . 1993. Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan.Edisi I. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Machmudin, Duswara. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa. Bandung : Refika Aditama. Magenda, Burhan (pengantar) dalam Amos Perlmutter. 2000. Militer dan Politik. Cet II. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Mahendra, Oka. 1996.Gugatan Dari Senayan Tentang Pemilu, DPR, HAM, Kolusi, Dan Korupsi. Denpasar : PT. Pustaka Manikgeni. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Jakarta : Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi. 2010. Mengawal Demokrasi dan Menegakan Keadilan Substansif ; Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
661
. 2010. Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002(Buku I, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945). Edisi Revisi. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. . 2010. Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku II Sendi-Sendi dan Fundamen Negara). Edisi Revisi. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. . 2010. Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002(Buku III, Jilid I, Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan). Edisi Revisi. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. . 2010. Naskah Komperhensif Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002(Buku III, Jilid II, Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan).Edisi Revisi. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. . 2010. Naskah Komperhensif Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002(Buku IV,Jilid I Kekuasaan Pemerintahan Negara). Edisi Revisi. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. . 2010. Naskah Komperhensif Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002(Buku IV, Jilid II Kekuasaan Pemerintahan Negara). Edisi Revisi. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. . 2010. Naskah Komperhensif Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002(Buku Jilid VIII,Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama). Edisi Revisi. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
662
. 2010. Frofil Mahkamah Konstitusi. Cet I. Jakarta : Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Machmmudin, Alwi Pribadi. 2003. Kandidat Seorang Presiden Dan Sebuah Konsep. Jakarta : The Adam Malik Center. Maksudi, Beddy Iriawan. 2012. Sistem Politik Indonesia : Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. IKIP Malang, Laboratorium Pancasila. 1979. Pokok-Pokok Pembahasan Pancasila : Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Cet II. Surabaya : Usaha Nasional. Mamun A Saefudin. 2009. Citra Indonesia Di Mata Dunia ; Gerakan Kebebasan Imformasi dan Diplomasi Publik. Cet I. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung Bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Kedua. Bandung : Alumni. Marbun, dan MD, Mahmud Moh. 2000. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Cet II. Yogyakarta : Liberty. Marbun, SF. 2003. Peradilan Tata Usaha Negara. Cet II. Yogyakarta : Liberty. Marbun, B.N. 1994. DPRD, Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya. Edisi Revisi. Jakarta : Erlangga. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Edisi XVII. Yogyakarta : CV Andi Offset. Marno dan Idris. M. 2009. Strategi dan Metode Pengajaran : menciptakan Keterampilan Mengajar Yang Efektif dan Edukatif. Cet III. Yogyakarta : ArRuss Media Group. Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta : Prenada Media Group. .1999. Menuju Sistem Kepartaian Inklusif dalam Memilih Partai Mendambakan Presiden ; Belajar Berdemokrasi Di Ufuk Milenium. Cet I. Bandung : Rosdakarya.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
663
Martaniah, Sri Mulyani. 1984. Motif Sosial Remaja Suku Jawa Dan Keturunan Cina Di Beberapa SMA Yogyakarta : Suatu Studi Perbandingan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Marpaung, Leden. 2009. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Cet VI. Jakarta : Sinar Grafika. . 1999. Menggapai Tertib Hukum Indonesia. Cet I. Jakarta : Sinar Grafika. . 2004. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana. Cet II. Jakarta : Sinar Grafika. Marpaung, Rusdi. 2005. Menuju TNI Profesional Tidak Berbisnis Dan Tidak Berpolitik (Perjalanan Advokasi RUU TNI). Cet I. Jakarta : Imparsial, Koalisi Keselamatan Masyarakat, LPP. Martin, Seymour dalam Robert Micheis. 1984. Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendecies of Modern Democracy. Terjemahan. Cet I. Jakarta : CV Rajawali. Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Cet III. Jakarta : Prenada Media Group. Maschab, Mashuri. 1983. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. Cet I. Jakarta : PT. Bina Aksara. Masoed, Mohtar dan MacAndrews. 2006. Perbandingan Sistem Politik. Cet XVI. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. . 2003. Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan. Cet IV. Jakarta : RajaGrafindo Persada. MD, Mahmud. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta. . 2009. Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta : RajaGrafindo Persada. . 2011. Politik Hukum di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : .RajaGrafindo Persada. . 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
664
. 2010.Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi. Edisi I. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Mertokusumo, Sudikno. 1996. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Edisi IV. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. . 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Ke VIII. Yogyakarta : Liberty. . 2006. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Cet IV. Yogyakarta : Liberty. dan Pitlo, A. 1993. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Cet I. Bandung : PT Citra Aditya Bandung Bekerjasama dengan Departemen Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayan dan The Asia Foundation. Mestoko, Sumarsono. 1985. Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa. Cet I. Jakarta : Sinar Harapan. Miller, David dan Siedentop, Larry. Editor. 1986. The Nature of Political Theory. Terjemahan. Cet I. Jakarta : CV Rajawali. Moekijat. 1985. Analisa Jabatan. Cet IV. Alumni : Bandung. Moekri, Ahmad Kurdi. 2007. Negara Hukum dalam Ujian. Cet I. Jakarta : Ka-tulistiwa Press. Moeljatno. 2005. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cet XXV. Jakarta : Bumi Aksara. . 2008. Asas- Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta. Montesquie. 2011. The Sprit of Laws (L Esprit des lois). Terjemahan. Cet VII. Bandung: Nusa Media. Morgenthau, Hans J. 1990. Politics Among Nations; The Struggle For Power and Piece. Terjemahan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Muchsan. 1982. Seri Hukum Administrasi Negara : Peradilan Administrasi Negara. Cet I. Yogyakarta : Liberty.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
665
Mudyahardjo, Redja. 2010. Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Mufid, Muhamad. 2007. Komunikasi dan Regulasi Penyiaran. Cet II. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Muhammad, Bushar. 1986. Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengatar. Cet VI. Jakarta : PT Pradnya Paramita. Muhtaj, Majjda El. 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan UUD 1945 Tahun 2002. Cet II. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Munti, Ratna Batara. 2008. Advokasi Kebijakan Pro Perempuan : Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan. Jakarta : PPS-UI. Muslimin, Amrah. 1980. Beberapa Azas-Azas Dan Pengertian Pokok tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi. Bandung : Alumni. Mustafa, Bachsan. 2001. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Murhani, Suriansyah. 2008. Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah. Cet I. Palangkaraya : Laksbang Mediatama. Mutis, Thoby. 2004. Pengembangan Koperasi : Kumpulan Karangan. Cet IV. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. MPRS. dan Depertemen Penerangan. 1960. Ringkasan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia. Djakarta : MPRS dan Menteri Penerangan. Naim, Ngainun dan Sauqi, Achmad. 2010. Pendidikan Multikultur ; Konsep dan Aplikasi. Cet II. Yogyakarta : AR Ruzz Media. Naja, Hasanuddin Rahman Daeng. 2004. Dewan Perwakilan Derah : Bicameral Setengah Hati. Cet I. Yogyakarta: Media Pressindo. Najih, Mokhamad. 2008. Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi : Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara. Cet I . Malang : In- TRANS Publising.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
666
Narwoko, J.Dwi dan Suyanto, Bagong (ed.). 2006. Sosiologi; Teks Pengantar Dan Terapan. Cet II. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Nasikun. 2005. Sistem Sosial Indonesia. Cet XIV. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Nasution. 2010. Didaktik Asas-Asas Mengajar. Edisi II.Jakarta : Bumi Aksara. Nasution, Adnan Buyungdkk. 2001.Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia(Major International Human Rights Instrument). Edisi II. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Nasroen, M. 1986. Ilmu Perbandingan Pemerintahan. Cet II. Jakarta : Aksara Baru. Nazriyah. 2007. MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan. Jakarta : Rajagrafindo. Negara, Tunggul Anshari Setia. 2008. Pengantar Hukum Pajak. Malang : Banyumedia Publishing. Noer, Deliar. 1983. Pengantar Ke Pemikiran Politik. Edisi Baru. Jakarta : CV. Rajawali Notonagoro. 1974. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Cet IV. Jakarta : Pantjuran Tudjuh. . 1982. Beberapa Mengenai Falsafah Pancasila. Cet II. Jakarta : Rajawali Pers. Notosusanto, Nugroho dkk. Editor. 1985. Tercapainya Konsensus Nasional 19661969. Cet III. Jakarta : PN Balai Pustaka. . 1984. Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Cet V. Jakarta : PN Balai Pustaka. Nurtjahjo, Hendra. 2006. Filsafat Demokrasi. Cet I.Jakarta : Bumi Aksara. . dan Fuad, Fokky. 2010. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Salemba Humanika. Van Dijk, R. 2006. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Cet IX. Bandung : Bandar Maju.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
667
Vyshinsky, Andrei Y. 1948. The Law of the soviet state. New York : The Macmillan Company. Rachels, James. 2008. The Elements of Moral Philosofi. Terjemahan. Cet V. Yogyakarta : Kanisius. Radjab, Dasril. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Renika Cipta. Rafar. J.H. 2002. Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiaveli. Cet II. Jakarta : Rajawali Pers. Ragawino. 2007. Hubungan Hukum Dengan Bangsa, Negara, Dan Kekuasaan. Bandung : Tanpa Penerbit. Rahardjo, Dawam.M. 2000. Independensi BI Dalam Kemelut Politik. Cet I. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo. Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. . 2009. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing. .1980. Hukum, Masyarakat, Dan Pembangunan. Cet II. Bandung : Alumni. Ranadireksa, Hendarmin. 2009. Visi Bernegara ; Arsitektur Konstitusi Demokratik. Cet I. Bandung : Fokus Media. Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. Cet I. Bandung : Mandar Maju. Rato, Dominikus. 2009. Pengantar Hukum Adat. Cet I. Yogyakarta : LaksBang Pressindo. Ricklief, M. C. 2007. A History Of Modern Indonesia. Terjemahan. Cet IX. Yogykarta : Gadjah Mada University Press. RifaI, Amzulian. Tt.Wajah Hakim Dalam Putusan : Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). Ridwan. HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
668
Ridwan dan Sodik. 2010. Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara Dan Hukum. Bandung : Nuansa. Rindjin, Ketut. 2009. Pendidikan Pancasila. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha. Renan, Ernes. 1994. Quest ce quune nation. Terjemahan. Cet I. Bandung : Alumni. Rohman, Arif. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Edisi I. Surabaya : Laksbang Mediatama. Roosadijo, Marmin Martin. 1982. Ekologi Pemerintahan di Indonesia. Bandung : Alumni. Rosseau, Jean-Jacques. 1989. Du Contract Social. Terjemahan. Cet I. Jakarta : Dian Rakyat. Rosyadi, Paul. 1984. Political Institution. Terjemahan. Jakarta : Ind-Hiil Co. Rudy, May. 2002. Hukum Internasional I. Cet I. Bandung : Refika Aditama. . 2009. Hukum Internasional II. Cet III. Bandung : Refika Aditama. Rukmini, Mien. 2009. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sebuah Bunga Rampai.Bandung: PT Alumni. Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2008. An Introducton to Political Sociologi. Terjemahan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Rusman. 2012. Model-Model Pembelajaran ; Mengembangkan Profesionalisme Guru. Edisi II. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Ryacudu, Ryamizard. 2011. Pancasila Mencari Konstruksi Pemahaman, Pengalaman Enam Tahun Pembasisan Pancasila. Cet I. Yogyakarta: Pergerakan Kebangsaan. Sadjijono. 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Aministrasi. Cet I. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo. Safaat, Muchamad Ali. 2011. Pembubaran Partai Politik; Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik. Cet I. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
669
Said, Umar. 2009. Pengantar Hukum Indonesia ; Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia. Cet II.Malang : Setara Press. Saidi, Muhammad Djafar. 2008. Hukum Keuangan Negara. Edisi I. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. . 2011. Hukum Keuangan Negara. Edisi Revisi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. . 2007. Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Edisi I. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Saifullah. 2007. Refleksi Sosiologi Hukum. Cet I. Bandung : Refika Aditama. Salle, H. Aminuddin. 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Cet I. Yogyakarta : Kreasi Total Media. Salim. 2009. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta : Sinar Grafika. Sanjaya, Wina. 2010. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. . 2010. Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan(KTSP). Jakarta : Kencana Prenada Media Group. . 2011. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Samidjo. 1985. Pengantar Hukum Indonesia ; Dalam Sistem SKS Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan. Bandung : CV Armico. Sanit, Arbi. 2011. Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan. Cet XV. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Sanusi, Achmad. 1984. Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Edisi IV. Bandung : Tarsito. Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2010. Kriminologi. Cet X. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Sarwono, Sarlito W. 2012. Pengantar Psikologi Umum. Edisi IV. Jakarta : PT. RajaGrafondo Persada.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
670
Sastropoetro, Santoso. 1988. Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Masssa. Cet II. Bandung : Alumni. Saud, Udin Syaefudin. 2011. Inovasi Pendidikan. Cet IV. Bandung : Alfabeta Saptaningrum, Indriaswati Dyah. 2011. Hak Asasi Manusia Dalam Pusaran Politik Transaksional ; Penilaian Terhadap Kebijakan HAM Dalam Produk Legilsasi Dan Pengawasan DPR RI Periode 2004-2009. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Sekertariat Jenderal MPR RI. 2007. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat. . 2011. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : Sekjen MPR RI. . 2011. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara Dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Cet X. Jakarta : Sekjen MPR RI. . : Sekjen MPR RI. . 1999. Buku Kedua Jilid 6 : Risalah Rapat Badan Pekerja Panitia Ad Hoc III Sidang UMUM MPR RI. Jakarta : Sekertariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sekertariat DPR RI. 2010. Rencana Strategis DPR RI 2010-2014. Jakarta : Sekertariat DPR RI. Sekertariat Negara. 1995. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei - 22 Agustus. Setiadi, Elly M dkk. 2010. Ilmu Budaya Dasar. Edisi Kedua. Cet VI. Jakarta : Prenada Media Group. Setiadi, Elly M. 2005. Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Cet II. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. . 2011. Undang-Undang Dasar 1945. Cet X. Jakarta
I Gusti Ngurah Santika, SPd
671
Setijo, Pandji. 2008. Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Siagian, Sondang P.1983. Adminsitrasi Pembangunan. Cet XI. Jakarta : PT. Gunung Agung. . 1983. Filsafat Administrasi. Cet XII. Jakarta : Gunung Agung. . 2001. Manajemen Stratejik. Cet IV. Jakarta : Bumi Aksara. Siahaan, Maruarar. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Edisi II. Jakarta : Sinar Grafika. Sibuea, Hotma P. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta : Erlangga. Sihaloha, Aberson Marle. 1999. Tragedi Wakil Rakyat; Perjuangan Menegakan Kedaulatan Rakyat. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Simajuntak, B. 1981. Tiga Undang-Undang Dasar RI dan Permasalahan. Cet I. Bandung : Tarsito. Simanungkalit, Parasian. 2004. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Ketahanan Nasional. Cet I. Jakarta : Yayasan Wajar Hidup. Sinaga, H. Obsatar. 2010. Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik : Implementasi Kerjasama Internasional. Bandung : Lepsindo. Situmorang, Victor dan Soedibyo. 1992. Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara. Cet II. Jakarta : Rineka Cipta. Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Cet V. Jakarta : Rineka Cipta. Soedirjo. 1985. Kasasi Dalam Perkara Perdata. Cet II. Jakarta : Akademika Pressindo. Soehino. 1984. Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
672
. 1985. Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. . 2007. Hukum Tata Negara, Hukum Perundang-undangan. Yogyakarta : BFE Yogyakarta. . 2010. Hukum Tata Negata : Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia. Edisi I. Yogyakarta : Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. . 1983. Ilmu Negara. Cet. III. Yogyakarta : Liberty. . 1984. Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan. Cet I. Yogyakarta : Liberty. Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Cet. XLIII. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. . 2009. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Cet. XVIII. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. . 2008. Hukum Adat Indonesia. RajaGrafindo Persada. Indonesia. dan Mamudji, Sri. 2009. Penelitian Hukum Normatif. Cet XI. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. dan Purbacaraka, Purnadi. 1993. Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum. Cet VI. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. .1993. Hukum. Cet VI. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. . 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cet IX. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. . 1989. Mengenal Sosiologi Hukum. Cet V. Bandung : Citra Aditya Bakti. . 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Cet I. Jakarta : CV Rajawali. Perihal Kaedah Cet IX. Jakarta: PT.
. 1981. Kriminologi Suatu Pengantar. Cet I. Jakarta : Ghalia
I Gusti Ngurah Santika, SPd
673
Soekarno. 1989. Indonesia Menggugat!. Cet III. Jakarta : Haji Masagung. Soemantri, Sri. 2006. Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi. Edisi Revisi. Bandung : Alumni. . 1979. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Cet I. Bandung : Alumni. . 1986. Hak Menguji Material Di Indonesia. Cet IV. Bandung : Alumni. . 1989. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Citra Aditya Bakti. . 1993. Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Cet I. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. . 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Cet I. Bandung : Alumni. . 1981. Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara. Edisi II. Jakarta : CV Rajawali. . 1985. Ketetapan MPR Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara. Bandung : Remadja Karya. Soemardi. 1986. Sumber-Sumber Hukum Positif. Cet III. Bandung: Alumni. Soemitro, H. Rochmat. 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Cet III. Bandung : PT. Eresco. . 1998. Peradilan Tata Usaha Negara. Cet IV. Bandung : PT. Refika Aditama. Soetomo. 1983. Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. Surabaya : Usaha Nasional. Soepomo. 1988. Sistem Hukum Di Indonesia. Cet. XIII. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. . 2005. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Cet. XVII. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
674
. 2003. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Cet XVI. Jakarta : PT Pradnya Paramita. . 1954. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Cet IV. Djakarta : Noordhoff-Kolff N.V. . 1983. Hubungan Individu Dan Masyarakat. Cet IV. Jakarta : PT Pradnya Paramita. Soeprapto, H.R. Riyadi. Tt. Buku Pengembangan Kapasitas Pemda Menuju Good Governance.Jakarta : tanpa penerbit. Sotikno. 2008. Filsafat Hukum Bagian II. Cet. X. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Sosronegaro, Herqiutanto dkk. 1984. Beberapa Ideologi Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Kenegaraan. Cet I. Yogyakarta : Liberty. Syofian, Syofrin dan Hidayat, Asyhar. 2004. Hukum Pajak dan Permasalahannya. Cet I. Bandung : Refika Aditama. Starke, J.G. 2008. Pengantar Hukum Internasional I. Edisi X. Cet IX. Jakarta : Sinar Grafika. .2008. Pengantar Hukum Internasional II. Edisi X. Cet VII. Jakarta : Sinar Grafika. Strong, C.F. 2005.Modern Political Constitutions : An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form. Terjemahan. Bandung : Nusa Media. Subagio, Mas. 1977. Beberapa Problema Hukum Pada Umumnya Dan Hukum Tata Negara Pada Khususnya. Bandung : Alumni. Subagyo, P. Joko. 2005. Hukum Laut Indonesia. Edisi Baru. Jakarta : Rineka Cipta. Subekti, R . 1989. Hukum Acara Perdata. Cet. III. Bandung : Binacipta. . 1994. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet XXVI. Jakarta : PT. Intermasa. . 1983. Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Cet III. Bandung : Alumni.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
675
Subekti, Valina Singka. 2008. Menyusun Konstitusi Transisi : Pergulatan Kepentingan Dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945. Edisi I. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. .1998. Wacana Reformasi Politik : Rekonstruksi dari Diskusi Publik dalam Mengubur Sistem Politik Orde Baru. Cet I. Bandung : Mizan. Sudarto. 1986. Hukum Dan Hukum Pidana. Cet IV. Bandung : Alumni. Sujamto. 1994. Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia. Cet II. Jakarta : Sinar Grafika. Sujanto, Agus. 2012. Psikologi Umum. Cet XVI. Jakarta : Bumi Aksara. Sukirno, Sadono. 2010. Ekonomi Pembangunan ; Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Edisi Kedua. Jakarta : Prenada Kencana Group. . 2010. Mikro Ekonomi ; Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Sunarno, Siswanto.2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sinar Grafika. Suny, Ismail. 1986. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Cet VI. Jakarta : Aksara Baru. Surajiwo dkk. 2010. Dasar-Dasar Logika. Cet V. Jakarta : Bumi Aksara. . 2008. Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia. Cet III. Jakarta : Bumi Aksara. Suriasumantri, Jujun S. 2009. Ilmu dalam Perspektif : Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu. Cet XVII. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. . 2003. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Cet XVII. Jakarta : Sinar Harapan. Susanto, Sewan. 1985. Perjuangan Tentara Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Suseno, Frans Magnis. 2010. Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Cet XXI. Yogyakarta : Kanisius. Sutrisno, Mudji. 2009. Ranah-Ranah Kebudayaan. Cet V. Yogyakarta: Kanisius.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
676
Sutrisno, Slamet. 2006. Filsafat Dan Ideologi Pancasila.Edisi I. Yogyakarta : CV Andi Offset. Supriatnoko. 2008. Pendidikan Kewarganegaraa ; Buku Ajar Untuk Perguruan Tinggi. Cet I. Jakarta : Penaku. Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. Hukum Konstitusi, Proses, dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002. Jakarta : Ghalia Indonesia. . 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Syam, Mohammad Noor. 1986. Filsafat Pendidikan Dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila. Cet III. Surabaya : Usaha Nasional. . 1987. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Edisi II. Yogyakarta : Liberty. Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. 2010. Dasar Dasar Politik Hukum. Edisi VI. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Tahija, Julius. 1997. Melintas Cakrawala: Kisah Sukes Pengusaha Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Taniredja. H. Tukiran.dkk. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif. Cet II. Bandung : Alfabeta. Tarmidji, Zaini, 1992. Capita Selecta Pemerintahan. Bandung : Angkasa. Thaib, Dahlan dkk. 2010. Teori Dan Hukum Konstitusi. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 1994. DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Cet I. Yogyakarta : Liberty. Thalhah,H.M. dan Malian, Sobirin. 2011. Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia. Cet I. Yogyakarta : Kreasi Total Media. Thoha, Miftah. 2011. Birokrasi Dan Politik Di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Tim Litbang Departemen Hukum dan HAM. 2005. Hak-Hak Kebebasan Berpolitik Bagi Anggota TNI Dan Polri. Jakarta : Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
677
Tim ICCE UIN. 2010. Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi. Edisi Ketiga. Jakarta : Prenada Media Group. Trianto dan Tutik, Titik Triwulan. 2007. Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan. Cet I. Jakarta : Prestasi Pustaka Publiser. Tumpa. 2010. Peluang dan Tantangan eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia. Cet I. Jakarta : Prenada Media Group. Tocqueville, Alexis De. 2005. Alexis De Tocquevelli on Democracy, Revolution, and Society. Terjemahan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Tutik, Titik Triwulan. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta : Cerdas Pustaka . 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta : Prenada Media Group. Dan Widodo, H.Ismu Gunadi. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Cet.I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Uno, H. Hamzah B. 2011. Profesi Kependidikan : Problem, Solusi, dan Reoformasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. . 2011. Teori Motivasi dan Pengukurannya : Analisis Di Bidang Pendidikan. Cet VII. Jakarta : Bumi Aksara. Urbaningrum, Anas. 2004. Melamar Demokrasi; Dinamika Politik Indonesia. Cet I. Jakarta : Republika. Utrecht, U. 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya : Pustaka Tinta Mas. Panyarikan, Ketut Sudiri. 1981. Pancasila Dalam Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Surabaya : Usaha Nasional. Pamudji, .S. 1985. Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional : Suatu Analisis di Bidang Politik dan Pemerintahan. Edisi Revisi. Jakarta : Bina Aksara. . 1983. Perbandingan Pemerintahan. Cet III. Jakarta Bina Aksara.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
678
Pamungkas, Sigit. 2011. Partai Politik ; Teori dan Praktik Di Indonesia. Yogyakarta: Institute Democracy And Welfarism. Poerwantana, P.K. 1994. Partai Politik Di Indonesia. Cet I. Jakarta : Rineka Cipta. Pradjodikoro, Wirjono. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Edisi II. Bandung : PT. Eresco Bandung. . 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Edisi Revisi. Bandung : PT. Refika Aditama. . 1984. Perbuatan Melanggar Hukum. Cet VII. Bandung : Sumur. . 1984. Hukum Laut Bagi Indonesia. Cet VIII. Bandung : Sumur. Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut. 1987. Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia. Jakarta : PT. Bina Aksara. . 1988. Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5/1986). Yogyakarta : Liberty. . 1986. Tindak Pidana Makar Menurut KUHP. Cet I. Bogor : Ghalia. Pringgodigdo. 1981. Tiga Undang-Undang Dasar. Cet V. Jakarta : PT. Pembangunan. Prinst, Darwan. 2001. Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Cet I. Bandung : Citra Aditya Bakti. Pudjosewojo, Kusumadi. 2004. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Cet X. Jakarta : Sinar Grafika. Pudyatmoko, Y. Sri. 2002. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta : Andi Offset. Purbopranoto, Kuntjoro. 1981. Perkembangan Hukum Aministrasi Indonesia. Cet I. Bandung : Angkasa Offset. Purbopranoto, Kuntjoro dalam Darji Darmodihardjo. 1991. Satiaji Pancasila. Edisi Revisi. Cet X. Surabaya : Usaha Nasional
I Gusti Ngurah Santika, SPd
679
Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1985. Renungan Tentangan Filsafat Hukum. Edisi Revisi. Cet. IV. Jakarta : CV Rajawali. Wahab, Abdul Aziz dan Sapria. 2011. Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Cet I. Bandung : Alfabeta. Weber, Max. 2006. From Max Weber: Essays in Sociology. Terjemahan. Cet I. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Widjaja, Ganawan. 2002.Seri Keuangan Publik ; Pengelolaan Harta Kekayaan Negara, Suatu tinjauan yuridis. Edisi I. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Widjaja, A.W. 1987. Tinjauan Undang-Undang Dasar : Indonesia, Malaysia, Singapura (Konstitusi Perbandingan). Cet I. Jakarta : Bina Aksara. Widja, I Gede. 2009. Pendidikan Sebagai Ideologi Budaya : Suatu Pengantar Ke Arah Pendidikan Kritis. Cet I. Denpasar : Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana kerjasama dengan Sari Kahyangan Indonesia. Widjaja, Wangsa dan Swasana, Meutia F. 1983. Mohammad Hatta Kumpulan Pidato II. Jakarta : PT.Idayu Press. Winardi. 2008. Dinamika Hukum, Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah. Cet I. Malang : Setara Press. Winarno. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Edisi Kedua : Jakarta : Bumi Aksara. Winataputra,Udin S. dan Budimansyah, Dasim. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, Dan Profil Pembelajaran. Cet I. Bandung: Widya Aksara Press Wheare, K.C. 2005. Modern Constitutions. Terjemahan. Bandung : Nusa Media. Widagdo, Setyo dan Widhiyanti, Nur Hanif. 2008. Hukum Diplomatik Dan Konsuler (Buku Ajar Untuk Mahasiswa). Cet I. Malang : Banyumedia Publising. Wiranata, I Gede A.B. 2005. Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa. Cet I. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Yasabari, Nasron. 1984. Bunga Rampai Hukum Dan Ekonomi. Bandung : Alumni.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
680
Yusdiansah, Efik. 2010. Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum. Bandung : CV Lubuk Agung. Zamroni. 2007. Pendidikan Demokrasi Dalam Transisi (Prakondisi Menuju Era Globalisasi. Cet I. Jakarta : PSAP Muhammadiyah. Zuchdi, Darmiyati. 2009. Humanisasi Pendidikan, Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi. Cet II. Jakarta : Bumi Aksara. Zuriah, Nurul. 2008. Pendidikan Moral dan Budi Pakerti Dalam Perspektif Perubahan (Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pakerti Secara Kontekstual dan Futuristik). Cet II. Jakarta : Bumi Aksara. JURNAL, MAJALAH, SKRIPSI, DAN DESERTASI Abdullah, Ujang. Uji Materiil Di Bawah Undang-Undang. Disampaikan pada Diklat Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara angkatan XIX. Hotel Purnama,Batu-Malang. 27 Nopember 2006. Affandi, Hernadi. Pengaturan dan Pelaksanaan Kebijakan Hukum Nasional Dalam Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia. Paper disampaikan dalam acara Pemantapan Wawasan Kader Partai Politik di Kabupaten Majalengka Tahun 2006, Majalengka, 11 Desember 2006 Ali, Mahrus. Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010. Alrasid, Harun. 1993. Masalah Pengisian Jabatan Presiden, Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai SidangMajelis Permusyawaratan Rakyat 1993. Desertasi UI. Aminah.Electoral Threshold Dan Parliamantery Threshold Sebagai Model Penyederhanaan Sistem Multi Partai Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009. Aminuddin, Muh. Zuman. Kebijakan Legilsatif Dalam Rangka Perlindungan Ideologi Dan Konstitusi Negara Dengan Hukum Pidana. 2006 (Skripsi). Asshiddiqie, Jimly. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangungan Hukum
I Gusti Ngurah Santika, SPd
681
Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan,diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003. Attamimi, A. Hamid S. 1990.Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis mengenai keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita IV. Desertasi Universitas Indonesia (tidak dipublikasikan). Argama, Rizky. 2006. Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Makalah. Universitas Indonesia. Azhar. Peranan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Kekuasaan Kehakiman. Inovasi Vol. 4/ XVII/Agustus 2005. Azhary, Aidul Fitraciada. Evaluasi Hasil Proses Amademen UUD 1945: Dari Demokratisasi Ke Perubahan Sistem.Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September 2006. Aziz, Machmud. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010. Chotidjah, Nurul. Eksetensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum Fak. Hukum UNISBA. Vol. XII. No. II. Juli 2010. Djafar, Wahyudi. Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum : Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010. Erwiningsih,Wibahyu. Peranan Hukum Dalam Pertanggung-jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuursandeling) Suatu Kebijakan Dalam Pembangunan Hukum. Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004. Fhaisal, Muhammad. Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia ; Sebuah Pencarian Teoritik.Jurnal llmu Sosial dan llmu Politik, Vol. 11, No. L, Juli 2007.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
682
Gerungan, Lucy K.F.R. Analisis Yuridis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dan Hubungannya Dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Vol.XIX/No.3/April 2011. Ghafur, Jamaludin. Penguatan Lembaga DPD Melalui Amandemen Ulang Lembaga MPR. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 14, Juli 2007. Ginting, Rasudyn. Struktur Pemerintahan Negara Republik Indonesia PascaAmandemen. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1, Januari April 2006. Gunawan, Winarno Adi. Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke 38 No. 3. Juli September 2008. Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa. Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya). Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010 Hanapiah, Pipin. Undang-Undang Dasar 1945. Makalah yang pernah disajikan pada Siswa Perwira Sekolah Staf dan Komando TNI-AU Angkatan XXXVIII Tahun Akademik 2001/2002, tanggal 5 Juni 2001 pada Sesko-AU, Lembang. Hantoro, Novianto Murti. Penafsiran Pasal33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian, Vol 14, No. 1. Maret 2009. Harjanti, Susu Dwi. Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol.I, No. 1, November 2009. Harun, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Tinjauan Hukum Islam. Suhuf. Vol. 20, No. 1, Mei 2008. Hasan, Zubairi. Memperbaiki Kualitas Pembentukan Undang-Undang (UU). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.4, No.2 -2007. Huda, Ni matul. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Perspektif Yuridis. Jurnal Hukum Republika, Vol 4, No 2, Tahun 2005.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
683
. Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan untuk Penguatan DPD dan Kekuasaan Kehakiman).Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15 Juli 2008. . Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010. Ilyas, Jazim. Implementasi Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945. Tesis 2008. Isharyanto. Watak UUD 1945 Dalam Kerangka Transisi Ke Demokrasi Di Indonesia. Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006. Isra, Saldi. Pemilihan Presiden Langsung Dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009. . Furification In Legislation Proccess Through Judicial Riview. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 7. No. 1 Maret 2010. .Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma dalam Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010. Junaidi, Veri. Pelanggaran Sistematis, Terstruktur Dan Masif : Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010. Jundiani. Kewenangan Kelembagaan Negara Setelah Perubahan UUD1945. De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 No. 1, Juni 2010. Kesowo, Bambang. Negara Hukum, Program Legislasi Nasional Dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya. Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kosmas, Ebu. Pemiiihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam SIstem Ketatanegaraan Indonesia.Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009. Kusuma, R.M. Ananda. Keabsahan UUD 1945 Pasca Amandemen. Jurnal Konstitusi, Vol.4, No. 1, Maret 2007. Latif, Abdul. Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil.Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
684
. Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multi Partai.Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009. Latupapua. Wajah Parlemen Indonesia (Antara Konsolidasi Terbatas Dan Demokrasi Semu). Hipotese, Vol. 2. No. 2, November 2008. Lotulung, Paulus. Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum. Denpasar 14-18 Juli 2003 : Makalah. Legowo, Tommi. A. Pemilihan Derah Secara Langsung, Good Governance Dan Masa Depan Otonomi Daerah.Jurnal Desentralisasi Vol. 6 No. 4 Tahun 2005. Maab, Muhammad Husnul dan Fauzan, Muhammad.Konsep Masyarakat Madani sebagai Solusi Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. dipresentasikan pada Simposium Nasional Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (SIMNAS ASIAN) ke-2 di Universitas Slamet Riyadi, Surakarta , pada tanggal 10 Pebruari 2012. Magnar, Kuntana, dkk. Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010. Mahmud, HM. Aksa. Komposisi Keterwakilan MPR Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Vol. I, No. I. Agustus 2009. Mahmud MD. Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan. Disampaikan pada Seminar Konstitusi Kontroversi Amandemen UUD 1945 dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Ketatanegaraan, yang diselenggrakan oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) di Jakarta, tanggal 12 April 2007. . Pengadilan Dan Demokrasi: Rabaan Diagnosis Dan Terapi. Disampaikan dalam dinner lecture yang diselenggarakan oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Hotel Ciptura Surabaya, Rabu 21 November 2007. Manan, Bagir. Pembaruan UUD 1945(Jurnal Magister Hukum: Vol. 2 No.1, Pebruari 2000). Marzuki, HM. Laica.Membangun Undang-Undang Yang Ideal. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.2-Juni 2007. . Paradigm Of PeopleS Sovereignity In The Changing Of Constitutional Year 1945. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7, No. I Maret 2010.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
685
. Pemakzulan Presiden/Wakil PresidenMenurut UndangUndang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010. . Kesadaran Berkonstitusi Dalam Kaitan Berkonstitusionalisme. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009. Marzuki, Masnur. Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya. Jurnal Hukum No.1 Vol.15 Januari 2008. Mawardi, M. Arsyad.Pengawasan Dan Keseimbangan Antara DPR Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jurnal Hukum No.1 Vol. 15 Januari 2008. Mezak, Meray Hendrik. Selayang Pandang Tinjauan Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan Amerika Serikat. Law Rivew, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. IX, No. I, Juli 2009. Monteiro, Josep M. Multi Partai Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2000 Muhtarom,Muhammad. Perkembangan Lembaga Peradilan Indonesia Di Era Reformasi.Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008. Muhsin, Habib. Penguatan Peran Masyarakat Dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009. Jurnal Ilmu Sosial Alternatif. Muntoha.Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syariah. Jurnal Hukum No.2 Vol.15 April 2008. Namira, Kiki. Perbandingan Kekuatan Politik Militer Era Orde Baru Dengan Era Reformasi. (Skripsi 2009 ). Nasution, Bahder Johan. Prosedur Perubahan UUD 1945 Kendala, Peluang Dan Langkah-Langkah. Majalah Hukum Forum Akademika. Vol.16, No.II, 2 Oktober 2007. Nasution, Mirza. 2009. Mempertegas Sistem Presidensial. Jurnal Konstitusi, Vo. 2, No. 1, Juni 2009. Nazaruddin. Kebijakan Multipartai Sederhana Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi, Volume I, Nomor 1, Juni 2009. Nazriyah, Riri. Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
686
Nugroho, Bagus Sigit. Pemilihan Umum Sebagai Wahana Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. (Skripsi 2011). Radjab, Dasril. Eksistensi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Majalah Hukum Forum Akademika. Volume 16 No. 2 Oktober 2007. Ranggawidjaja, Rosjidi. Kaji Ulang Tolok Ukur Penetapan Daerah Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2009. Rahayu, Derita Prapti. Politik Hukum Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. MMH, Jilid 36, No. 4, Desember 2007. Rai, I Gusti Agung. Peran Badan Pemeriksaan Keuangan Dalam Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara.Makalah ini disampaikan dalam rangka Sosialisasi Terpadu Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada 13 Perwakilan RI Luar Negeri, di Cairo, Mesir, tanggal 17 s.d. 21 Desember 2008. Rajagukguk, Erman. Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara. Disampaikan pada Diskusi Publik Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006. Ratna, Hernalia. Implementasi Politik Hukum Dalam Amandemen UUD 45 Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Perspektif Hukum, Vol.VI, No. II, November 2006. Rindawan, I Ketut. Implementasi Hukum Responsif Dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jurnal Kajian Pendidikan,FKIPUniv.Dwijendra, Desember 2010. Ristawati, Rosa. Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensial. Jurnal Konstitusi, Vol 2, No. 1 Juni 2009. Rosyadi, Imron. Gagasan Dan Praktik Politik Islam Era 1966 1990 An Dalam Perspektif Orde Baru.SUHUF, Vol. 20, No. 2, Nopember 2008. Sanit, Arbi. Penguatan Sistem Politik Dan Pemerintahan Presidensial. Majalah Figur, Edisi XI/ Tahun 2007.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
687
Santika, I Gusti Ngurah. Revitalisasi Pancasila Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan. Makalah disampaikan dalam rangka Bulan Bung Karno di Gor Kapten Sujana (Lapangan Buyung) Jl. Gunung Agung Denpasar 2012. . Amandemen UUD 1945 Serta Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Makalah disampaikan dalam seminar alumni FKIP Universitas Dwijendra di Aula Dwijendra Denpasar 2012. Saptaningrum, Indriaswati Dyah. Kuasa Hierarki Perundang-Undangan Dalam Republik Desa Attamimi. Juli September 2006 . Edisi XII Tahun III. Jentera. Santoso, Purwo. Amandemen Konstitusi Untuk Mengelola Kebhinekaan Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.10, No.3, Maret 2007. Setiyono, Agus Budi. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah. (2008 Skripsi). Sidqi, Sexio Yuni Noor. Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parlementarian). Jurnal Hukum No. 1 Vol. 15 Januari 2008. Sihombing, Eka N.A.M. Pemberlakuan Parliametary Threshold Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, Volume I, Nomor 1, Juni 2009. Simbolon, Marudut. Partai Politik Dan Sistem Politik (Suatu Studi Transformasi Pemikiran Dan Teori Analisis Sistem Politik A. Almond Dalam Perspektif Politik Pemerintahan SBY- JK) 2008. (Skripsi). Sinaga, Obsatar. Kebijakan dan Agenda Reformasi Birokrasi. Administratur,Vol. 1 \ No. 4 Januari 2008. . Implementasi Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Peranan Lembaga Negara dalam Membangun NKRI. Administratur, Vol. 1, No. 3, Agustus 2007. Sjuhad, Miftachus. Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional. Jurnal Konstitusi, Vol. 2, No. 1, Juni 2009. Soebarjo. Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sisitem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia. Jurnal Hukum No.1 Vol. 14 Januari 2007.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
688
Stefanus, Kotan Y. Dilema Penentuan Calon Anggota Legislatif.Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009. Suadana, I Wayan. TinjauanNormatif Naskah Proklamasi Sebagai Dasar Pembentukan Hukum. (Skripsi 2011). Sunaryo, Sidik. Ambiguitas ISu Hukum Dan Keadilan ( Sisi Lain ari Pemilihan Presiden).Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009. Sutiyoso, Bambang. Peran Partai Politik Dalam Mendukung Tegaknya Supremasi Hukum.Fenomena:Vol. 4 No. 2September 2006. Supriyanto, Hadi. Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif Dan Yudikatif. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.1, No. 1. Juli 2004. Utama, Yos Johan. Mengugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan Dalam Perkara Administrasi Negara (Suatu Studi Kritis terhadap Penggunaan Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Peradilan Administrasi). Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007. Pulukadang, Ishak dan Sitanggang, Efendi.P. Demokrasi Dan Desentralisasi Di Era Reformasi : Konsep, Dampak Implementasi, dan Pemantapannya. Fasific Jurnal. Maret 2008. Vol. 2(2). Purwoko. Sistem Politik Dan Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi. DiterbitkanOleh : Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. POLITIKA, Vol. I,No. 1, April 2010. Wardhani, Sri Handayani Retna. Optimalisasi Partai Politik Dalam Membangun Pemilu Yang Demokratis. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009. Wibawanti, Erna Sri. Saatnya Electoral Threshold Dilaksanakan Secara Konsisten Menuju Multi Partai Terbatas. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009. Widarsono. 2002. Pergesaran Kekuasaan Pada Perubahan UUD 1945 Dan Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Periode 1999 Sampai Dengan 2002. Tesis UI (tidak dipublikasikan). Wijaya, Arif. Kedudukan Norma Hukum Dan Agama Dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila. Al-Qnn, Vol. 11, No. 2, Desember 2008.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
689
Wiyanto, Andy. Pertanggungjawaban Presiden Dan Mahkamah Konstitusi.Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010. Wiyono, Suko. Pemilu MultiPartai Dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol 2, No. 1, Juni 2009. Yarani, Meri. Hubungan DPD Dengan Lembaga Negara Lain Dalam Memaknai Checks And Balances. Majalah Hukum Forum Akademika. Vol. 16. No. 2. Oktober 2007. Yudhanta, A.A. Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Skripsi Undwi 2011). PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 8 Tahun 2012, LN No. 117 Tahun 2012, TLN No. 5326. , Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316. , Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 8 Tahun 2011, LN No. 70 Tahun 2011, TLN No. 5226. , Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 27 Tahun 2009, LN No. 123 Tahun 2009, TLN No. 5043. , Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, UU No. 22 Tahun 2004, LN No. 89 Tahun 2004, TLN No. 4415. , Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, UU No. 18 Tahun 2011, LN No. 106 Tahun 2011, TLN No. 5250. , Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No.4389.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
690
, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234. , Undang-Undang tentang Grasi, UU No 22 Tahun 2002, LN No. 108 Tahun 2002, TLN No. 4234. , Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, UU No. 5 Tahun 2010, LN No. 100 Tahun 2010, TLN No. 5150. , Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 3 Tahun 2009, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958. ,Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan, UU No. 20 Tahun 2009, LN No. 94 Tahun 2009, TLN No. 5023. , Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden, UU No 19 Tahun 2006, LN No. 108 Tahun 2006, TLN No. 4670. , Undang-Undang tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2008, LN No. 2 Tahun 2008, TLN No. 4801. , Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2011, LN No. 8 Tahun 2011, TLN No. 5189. , Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No 2951. , Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 34 Tahun 2004, LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439. , Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 No. 1999. TLN No. 3886. , Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN 4437. , Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 12 Tahun 2008, LN No. 59 Tahun 2008, TLN No. 4884.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
691
, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012. , Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043. , Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654. , Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2006, LN No. 63 Tahun 2006, TLN No. 4634. , Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 20 Tahun 2003, LN No. 78 Tahun 2003, TLN No.4301.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
692
BIODATA PENULIS
I Gusti Ngurah Santika S.Pd, lahir di Yeha 1 Agustus 1988. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan I Gusti Ngurah Oka dan I Desak Ayu Putu. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Peringsari (1996-2002) kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Selat (2002-2005) dan pendidikan menengah di SMAN 1 Selat (2005-2008) kemudian pada perguruan tinggi (2009-2012). Setelah menyelesaikan pendidikan SMA kemudian bekerja sebagai security pada PT Arkadena sampai januari 2012. Pada saat yang bersamaan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi sambil bekerja, akhirnya lulus dengan predikat cum laude. Kemudian untuk sekarang ini penulis belum bekerja, namun sedang melanjutkan pendidikan pada program Pasca Sarjana Undhiksa. Pengalaman penulis selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi adalah sebagai nara sumber dalam temuwicara menyambut bulan Bung Karno yang diselenggarakan Gor Kapten Sujana (Lapangan Buyung) Kota Denpasar (2012). Nara sumber dalam seminar alumni FKIP Universitas Dwijendra (2012), Mahasiswa berprestasi Prodi PKn, sebagai salah satu pemenang karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dikti. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti seminar-seminar yang berhubungan dengan bidang studi yang di dalami. Berkaitan dengan kritik dan saran terhadap tulisan ini, dapat disampaikan langsung kepada penulis dengan menghubungi alamat maupun no hp yang ada di bawah ini. Alamat rumah : Banjar Dinas Padang Aji Tengah, Peringsari, Selat Karangasem. No. Hp : 085237832582/085738693121.
I Gusti Ngurah Santika, SPd
Anda mungkin juga menyukai
- LK.9 Sistematika Laporan Best PracticeDokumen17 halamanLK.9 Sistematika Laporan Best PracticeSriBelum ada peringkat
- Buku Panduan Outing Class 2023Dokumen23 halamanBuku Panduan Outing Class 2023bagustribudiono155Belum ada peringkat
- Modul Ajar Informatika - Berpikir Komputasional - Fase EDokumen18 halamanModul Ajar Informatika - Berpikir Komputasional - Fase ENoviatun Padilah UIN MataramBelum ada peringkat
- Lembar Pengamatan Penilaian SikapDokumen12 halamanLembar Pengamatan Penilaian Sikaptriyanti mandasariBelum ada peringkat
- Modul Ajar Analisis DataDokumen83 halamanModul Ajar Analisis DataTiara Dewanti OfficialBelum ada peringkat
- Askeb Nifas Postpartum Hari Ke V RecoveredDokumen52 halamanAskeb Nifas Postpartum Hari Ke V RecoveredRhunu GeraBelum ada peringkat
- ALK-635-668 en IdDokumen34 halamanALK-635-668 en IdELSA MONICA YULIYANTOBelum ada peringkat
- Rilis Nilai - Literasi B. Inggris - Purpose of The TextDokumen7 halamanRilis Nilai - Literasi B. Inggris - Purpose of The TextAbdullah AzamBelum ada peringkat
- Modul 10Dokumen38 halamanModul 10Nurmiati BiantoroBelum ada peringkat
- Rincian K3 SoedarsoDokumen4 halamanRincian K3 SoedarsoAgus KenzieBelum ada peringkat
- Modul Ajar Kurmer Aksi 4 Sri Hardianti SahputriDokumen6 halamanModul Ajar Kurmer Aksi 4 Sri Hardianti SahputrisrihardiantisahputriBelum ada peringkat
- Power Points PresentasiDokumen35 halamanPower Points PresentasiWahyuBelum ada peringkat
- Mekatronika Dan AplikasinyaDokumen6 halamanMekatronika Dan AplikasinyaYayan FunkBelum ada peringkat
- Tips WawancaraDokumen14 halamanTips WawancaraZuraida Dwii Soetjipto100% (1)
- ALK - Bab 10Dokumen6 halamanALK - Bab 10taniaBelum ada peringkat
- PDF Chapter 24 Completing The Auditdocx CompressDokumen5 halamanPDF Chapter 24 Completing The Auditdocx CompressFullof ShitBelum ada peringkat
- Modul Ajar Informatika 2 - Teknologi Informasi Dan KomputerDokumen18 halamanModul Ajar Informatika 2 - Teknologi Informasi Dan Komputertkj752Belum ada peringkat
- Informatika Bs Kls X RevDokumen272 halamanInformatika Bs Kls X RevRiska Maharani22Belum ada peringkat
- Prinsip Archimedes Dan Newton Pada Kapal LautDokumen5 halamanPrinsip Archimedes Dan Newton Pada Kapal LautsaptianBelum ada peringkat
- Anatomi Dan Fisiologi TumbuhanDokumen4 halamanAnatomi Dan Fisiologi Tumbuhanmuhammad hairunBelum ada peringkat
- Instrumen Supervisi Pembelajaran Kurikulum 2006 KTSPDokumen6 halamanInstrumen Supervisi Pembelajaran Kurikulum 2006 KTSPJuliantoBelum ada peringkat
- Modul Ajar Informatika 1 - Berpikir KomputasionalDokumen15 halamanModul Ajar Informatika 1 - Berpikir KomputasionalvikililiBelum ada peringkat
- Lembar Observasi PembelajaranDokumen3 halamanLembar Observasi PembelajaranRatnaBelum ada peringkat
- Informatika BG Kls ViiDokumen266 halamanInformatika BG Kls Viiyuniza shafarinaBelum ada peringkat
- MODUL AJAR BK InformatikaDokumen15 halamanMODUL AJAR BK InformatikaAbi KiatanBelum ada peringkat
- Tugas 1Dokumen17 halamanTugas 1kasmaBelum ada peringkat
- GDD Template AmikomDokumen9 halamanGDD Template AmikomUri NurcahyaniBelum ada peringkat
- SMK3-003 Identifikasi Dan Inventarisasi Per-UU K3Dokumen5 halamanSMK3-003 Identifikasi Dan Inventarisasi Per-UU K3bobby hirawanBelum ada peringkat
- Askeb ANCDokumen18 halamanAskeb ANCriniBelum ada peringkat
- E Book Ea Wawancara Kerja Updated 2Dokumen19 halamanE Book Ea Wawancara Kerja Updated 2Arum JakilaBelum ada peringkat
- Modul Ajar Informatika - SKDokumen19 halamanModul Ajar Informatika - SKAhm. SyahidinBelum ada peringkat
- Telaah Video PembelajaranDokumen5 halamanTelaah Video PembelajaranHendriBelum ada peringkat
- Keracunan Makanan-Modul PencernaanDokumen37 halamanKeracunan Makanan-Modul PencernaanWahyudi Bambang SukocoBelum ada peringkat
- Modul Pelatihan AdminDokumen36 halamanModul Pelatihan AdminRaihan Achyar RBelum ada peringkat
- Rubrik Penilaian Sikap Sosial Sma Dan MaDokumen28 halamanRubrik Penilaian Sikap Sosial Sma Dan MaUcuAyezBelum ada peringkat
- Surat Edaran OutingclassDokumen2 halamanSurat Edaran Outingclassazhimah zhaharaBelum ada peringkat
- MODUL AJAR M. ANWAR S Informatika Bab 2 - Berpikir KomputasionalDokumen12 halamanMODUL AJAR M. ANWAR S Informatika Bab 2 - Berpikir Komputasionalanwar samsudinBelum ada peringkat
- Final Ma Tik Sahrudin D Rev2Dokumen77 halamanFinal Ma Tik Sahrudin D Rev2Mia NoviantiBelum ada peringkat
- 100 Soal Persiapan Ujian Seleksi PPG 2018 Kompetensi PedagogikDokumen22 halaman100 Soal Persiapan Ujian Seleksi PPG 2018 Kompetensi Pedagogikiis nurrahmawatiBelum ada peringkat
- LK 3..telaah Video Pembelajaran Dan PeerteachingDokumen8 halamanLK 3..telaah Video Pembelajaran Dan PeerteachingPrima Hasti KurniasariBelum ada peringkat
- Modul Elemen Dsi - Septi WDokumen19 halamanModul Elemen Dsi - Septi WSepti WulandariBelum ada peringkat
- Analisis KreditDokumen34 halamanAnalisis KreditCleoBelum ada peringkat
- SMK Informatika BG KLS X 4Dokumen272 halamanSMK Informatika BG KLS X 4Farel napuBelum ada peringkat
- Buku Pendidikan Karakter FinalDokumen154 halamanBuku Pendidikan Karakter FinalHerman Yoseph WSBelum ada peringkat
- SK HivDokumen3 halamanSK HivRulanti MulaniBelum ada peringkat
- Modul 11Dokumen62 halamanModul 11Nurmiati BiantoroBelum ada peringkat
- Askeb BBL NormalDokumen20 halamanAskeb BBL NormalAdityaPratiwiBelum ada peringkat
- Mekatronika Sistem PenggerakDokumen9 halamanMekatronika Sistem PenggerakKiswahBelum ada peringkat
- Artikel Penjernihan AirDokumen10 halamanArtikel Penjernihan AirLubna Syarifah23Belum ada peringkat
- Aplikasi PresentasiDokumen6 halamanAplikasi PresentasiRisma HarizaBelum ada peringkat
- Rumus Fungsi Microsoft Excel Lengkap Contoh Dan PenjelasanDokumen11 halamanRumus Fungsi Microsoft Excel Lengkap Contoh Dan PenjelasanHiyar KkuBelum ada peringkat
- Dasar Adobe Photoshop™Dokumen25 halamanDasar Adobe Photoshop™chrisdyansyah100% (12)
- Modul Belajar AD (Analisa Data)Dokumen42 halamanModul Belajar AD (Analisa Data)puskom kitaBelum ada peringkat
- Berpikir Komputasional: InformatikaDokumen15 halamanBerpikir Komputasional: InformatikaRahmat RamadhanBelum ada peringkat
- Tik Kelas ViiiDokumen64 halamanTik Kelas ViiiSartika Lestari Kyky DaulayBelum ada peringkat
- RPS KewirausahaanDokumen6 halamanRPS Kewirausahaanwiwit vitaniaBelum ada peringkat
- Makalah Pancasila Sistem FilsafatDokumen25 halamanMakalah Pancasila Sistem FilsafatDarmanto PrioBelum ada peringkat
- Makalah Manusia Indonesia Yang Seutuhnya FixedDokumen11 halamanMakalah Manusia Indonesia Yang Seutuhnya FixedsuryabimawardhaBelum ada peringkat
- BUKU20HUKUM20TATA20NEGARADokumen368 halamanBUKU20HUKUM20TATA20NEGARAelisyakartyasaBelum ada peringkat
- Makalah PancasilaDokumen27 halamanMakalah PancasilaNurul Maharani PutriBelum ada peringkat