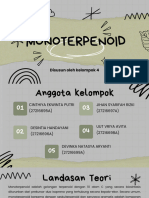PDF
Diunggah oleh
Yusi Triyani SupriyantiJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
PDF
Diunggah oleh
Yusi Triyani SupriyantiHak Cipta:
Format Tersedia
TEKNIK PEMISAHAN KOMPONEN EKSTRAK PURWOCENG SECARA KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS Eni Hayani1 dan May Sukmasari2
urwoceng (Pimpinella alpina Kds) merupakan tanaman obat. Seluruh bagian tanaman purwoceng dapat digunakan sebagai obat tradisional, terutama akar. Akarnya mempunyai sifat diuretika dan digunakan sebagai aprosidiak (Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1987), yaitu khasiat suatu obat yang dapat meningkatkan atau menambah stamina. Pada umumnya tumbuhan atau tanaman yang berkhasiat sebagai aprosidiak mengandung senyawa-senyawa turunan saponin, alkaloid, tanin, dan senyawa-senyawa lain yang berkhasiat sebagai penguat tubuh serta memperlancar peredaran darah. Di Indonesia tumbuhan atau tanaman obat yang digunakan sebagai aprosidiak lebih banyak hanya berdasarkan kepercayaan dan pengalaman (Hernani dan Yuliani 1991). Purwoceng banyak tumbuh secara liar di kawasan Dieng pada ketinggian 2.000-3.000 m dpl. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (1987), sebaran tanaman purwoceng di Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Wahyuni et al . (1997) menyatakan bahwa purwoceng dapat tumbuh di luar habitatnya seperti di Gunung Putri Jawa Barat dan mampu menghasilkan benih untuk bahan konservasi. Potensi tanaman purwoceng cukup besar, tetapi masih terkendala oleh langkanya penyediaan benih dan keterbatasan lahan yang sesuai untuk tanaman tersebut (Yuhono 2004). Pemisahan ekstrak purwoceng dapat menggunakan teknik kromatografi lapis tipis (KLT). Teknik ini merupakan suatu cara pemisahan komponen senyawa kimia di antara dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam (Kartasubrata 1987). Teknik tersebut hingga saat ini masih digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa kimia, karena murah, sederhana, serta dapat menganalisis beberapa komponen secara serempak (Hernani 1999). Teknik standar dalam melaksanakan pemisahan dengan KLT diawali dengan pembuatan lapisan tipis adsorben pada permukaan plat kaca (Institut Teknologi Bandung 1995). Tebal lapisan bervariasi, bergantung pada analisis yang akan dilakukan (kualitatif atau kuantitatif).
1
Pemisahan komponen kimia dari ekstrak purwoceng secara KLT bertujuan untuk mengetahui komponen-komponen yang terdapat dalam ekstrak tersebut. Percobaan dibuat dengan berbagai pereaksi (eluen) untuk mengetahui eluen atau pereaksi yang dapat memperoleh komponen terbanyak dari ekstrak purwoceng.
BAHAN DAN METODE Percobaan dilaksanakan di laboratorium Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat pada bulan Juli- September 2003. Peralatan yang digunakan antara lain adalah gelas piala, pengaduk, plat kaca, spreader , oven, neraca, pipet, pipet kapiler, dan bejana pengembang. Purwoceng yang diamati berasal dari ekstrak metanol akar dan daun. Tanaman purwoceng yang telah digiling, ditimbang 100 g lalu dimasukkan ke dalam gelas piala, ditambahkan 300 ml metanol, dan dikocok selama 2 jam. Campuran lalu didiamkan semalam dan disaring. Ampasnya ditambah metanol 100 ml lalu dikocok selama 2 jam, didiamkan semalam, filtratnya disatukan, ampasnya ditambahkan lagi 100 ml metanol, dikocok selama 2 jam, didiamkan semalam, filtratnya disatukan kemudian seluruh filtrat dipekatkan dengan menggunakan evaporator. Beberapa pereaksi atau eluen digunakan untuk memperoleh eluen yang tepat untuk pemisahan komponen dari ekstrak purwoceng. Eluen yang digunakan adalah: (1) heksana : diklorometan (DCM) : metanol (MeOH) = 20:10 :1; (2) sikloheksana : etil asetat = 4:1; (3) toluen : eter = 1:1; (4) sikloheksana : aseton = 2:1; (5) eter : sikloheksana = 1:1; (6) etil asetat : toluen = 4:6; (7) sikloheksana : aseton : toluen = 2:1:0,5; serta (8) toluen : etil asetat : sikloheksana = 3:1:1. Eluen yang diperlukan adalah 30 ml larutan pereaksi dalam bejana pengembang untuk memisahkan komponen dalam ekstrak yang telah diteteskan pada plat kaca silica gel. Sebagai contoh penggunaan pereaksi sikloheksan : etil asetat = 4 : 1 adalah campuran 24 ml sikloheksan dan 6 ml etil asetat yang terdapat dalam bejana pengembang. Begitu pula campuran beberapa pereaksi untuk keperluan proses pengembangan dalam bejana.
Teknisi Litkayasa Penyelia dan 2 Teknisi Litkayasa Pelaksana pada Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah, Jalan Tentara Pelajar No. 3, Bogor 16111, Telp. (0251) 321879, Faks. (0251) 327010
Buletin Teknik Pertanian Vol. 10. Nomor 2, 2005
83
Adsorben sebagai fase diam yang digunakan yaitu silica gel 60 GF254 yang ketebalan pada plat 250m. Pendeteksi komponen adalah H2SO4 50% dan KOH 10% dalam alkohol. Pada media fase diam (plat kaca) yang telah dilapisi silica gel 60 GF 254 setebal 250 m diteteskan contoh ekstrak purwoceng dengan menggunakan pipet kapiler pada jarak 1,5 cm dari bagian bawah plat. Selanjutnya plat dimasukkan ke dalam bejana pengembang yang telah berisi pereaksi atau eluen jenuh, didiamkan sehingga batas eluen sekitar 15 cm dari awal penetesan pada plat kaca atau media fase diam yang berukuran 20 cm x 20 cm. Plat kaca lalu diangkat hingga pereaksi atau eluen menguap semua pada suhu kamar. Komponen atau spot yang terdapat pada plat diamati di bawah lampu ultra violet atau disemprot pereaksi penampak noda, dipanaskan dalam oven pada suhu 105 oC selama 10 menit. Setelah dingin diukur harga Rf dari masing-masing komponen. Harga Rf adalah perbandingan tinggi eluen pada plat silica gel dengan tinggi spot. Rf = tinggi spot (komponen) tinggi larutan pengembang
Hasil pemisahan ekstrak purwoceng dengan beberapa jenis eluen dan penampak noda H 2SO 4 50% menunjukkan hasil yang bervariasi. Untuk ekstrak daun, komponen terbanyak (12 komponen) diperoleh dengan menggunakan eluen sikloheksana dan etil asetat dengan perbandingan 4:1, dan yang paling sedikit (satu komponen) dengan eluen eter dan sikloheksan 1:1. Untuk ekstrak akar, komponen terbanyak (delapan komponen) diperoleh dengan menggunakan eluen heksan, diklorometana dan metanol 20:10:1, dan terendah (dua komponen) dengan eluen eter dan sikloheksan 1:1 (Tabel 1). Dengan demikian, penggunaan eluen eter dan sikloheksana 1:1 menghasilkan jumlah komponen paling rendah baik pada ekstrak daun maupun akar. Pemisahan komponen dari ekstrak daun dan akar purwoceng dengan menggunakan dua jenis eluen dan penampak KOH 10% dalam alkohol memberikan hasil yang relatif sama. Namun penggunaan eluen toluen, etil asetat, dan sikloheksana dengan perbandingan 3:1:1 memberikan hasil yang lebih tinggi, baik pada ekstrak daun maupun ekstrak akar (Tabel 2).
KESIMPULAN DAN SARAN HASIL DAN PEMBAHASAN Pemisahan komponen dengan KLTdipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu ruang, kejenuhan uap pereaksi, ketebalan fase diam, dan cara penetesan contoh ekstrak. Kromatografi adsorbsi umumnya lebih mudah dilaksanakan karena polaritas adsorbennya tetap, sehingga pemisahan dapat dilaksanakan dengan memanipulasi polaritas pelarutnya (Adnan 1997). Harga Rf dari setiap komponen dapat dibaca setelah plat silica gel tersebut disemprot dengan pereaksi pembangkit warna (penampak noda). Komponen ekstrak daun purwoceng yang terbanyak (12 komponen) diperoleh dengan eluen sikloheksana dan etil asetat 4:1 dengan pembangkit noda H 2SO 4 50%. Untuk ekstrak akar, komponen terbanyak (13 komponen) diperoleh dengan eluen toluene, etil asetat dan sikloheksana 3:1:1 dengan pembangkit noda KOH 10% dalam alkohol. Dengan pembangkit noda KOH 10% dalam alkohol, komponen ekstrak daun dan akar pada eluen toluene, etil asetat dan sikloheksana 3:1:1 terpisah secara jelas. Pada setiap pemisahan ekstrak daun dan ekstrak akar, komponen
Tabel 1. Pemisahan komponen dari ekstrak daun dan akar purwoceng dengan menggunakan pereaksi penampak H 2SO 4 50% Eluen Ekstrak daun Heksan : diklorometana : metanol = 20:10:1 Sikloheksana : etil asetat = 4:1 5 komponen: 0,13; 0,24; 0,41; 0,87; 0,97 12 komponen: 0,10; 0,26; 0,32; 0,39; 0,42; 0,45; 0,48; 0,52; 0,58; 0,58; 0,77; 0,93 5 komponen: 0,03; 0,07; 0,17; 0,70; 0,77 4 komponen: 0,35; 0,50; 0,59; 0,81 1 komponen: 0,13 Jumlah komponen dan harga Rf Ekstrak akar 8 komponen: 0,03; 0,09; 0,20; 0,23; 0,60; 0,83; 0,84; 0,97 6 komponen: 0,29; 0,45; 0,61; 0,81; 0,90; 0,92 7 komponen: 0,03; 0,07; 0,10; 0,27; 0,33; 0,60; 0,70 6 komponen: 0,26; 0,32; 0,55; 0,59; 0,85; 0,91 2 komponen: 0,07; 0,10
Toluen : eter = 1:1 Sikloheksana : aseton = 2:1 Eter : sikloheksana = 1:1
84
Buletin Teknik Pertanian Vol. 10. Nomor 2, 2005
Tabel 2. Pemisahan komponen ekstrak daun dan akar purwoceng dengan eluen yang berbeda dan penampak KOH 10% dalam alkohol Eluen Ekstrak daun Sikloheksana : aseton : toluen = 2:1:0,5 Toluen : etil asetat : sikloheksana = 3:1:1 10 komponen: 0,03; 0,23; 0,32; 0,38; 0,44; 0,65; 0,73; 0,76; 0,82; 1,00 11 komponen: 0,06; 0,12; 0,21; 0,26; 0,35; 0,47; 0,56; 0,62; 0,71; 0,82; 1,00 Jumlah komponen dan harga Rf Ekstrak akar 11 komponen: 0,03; 0,09; 0,41; 0,50; 0,59; 0,65; 0,70; 0,76; 0,79; 0,88; 1,00 13 komponen: 0,03; 0,12; 0,15; 0,35; 0,47; 0,73; 0,76; 0,85; 0,88; 0,91; 0,94; 0,97; 1,00
terbanyak diperoleh dari ekstrak akar kecuali pada eluen sikloheksana dan etil asetat 1:4. Jenis komponen pada ekstrak belum dapat diidentifikasi. Percobaan ini perlu dilanjutkan dengan pemisahan komponen secara kolom menggunakan pelarut toluen, etil asetat dan sikloheksana 3:1:1 yang diketahui mampu menghasilkan komponen lebih banyak dan terpisah dengan jelas. Pemisahan secara kolom dapat mengetahui jenis komponen dengan menggunakan GCMS.
Hernani. 1999. Teknik identifikasi bahan aktif pada tumbuhan obat. Makalah pada Seminar Pendalaman Materi di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Bogor. 13 hlm. Hernani dan Yuliani S. 1991. Obat-obat aprosidiak yang bersumber dari bahan alam. Prosiding Seminar Pelestarian Pemanfaatan Tumbuhan Obat dan Hutan Tropis Indonesia. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. hlm. 130-134. Institut Teknologi Bandung. 1995. Analisis Obat secara Kromatografi dan Mikroskopi (Terjemahan). Institut Teknologi Bandung. hlm. 256. Kartasubrata, Y. 1987. Dasar-dasar kromatografi. Makalah pada Kursus Metode Analisis Instrumental. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kimia Terapan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bandung. 17 hlm. Wahyuni, S, S. Koerniati, dan Nasrun. 1997. Konservasi tanaman obat langka purwoceng. Warta Perhipba 5: 8-11. Yuhono, J.T. 2004. Usaha tani purwoceng, Potensi, peluang dan masalah pengembangannya. Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 15: 25-32.
DAFTAR PUSTAKA
Adnan, M. 1997. Teknik Kromatografi untuk Analisis Bahan Makanan. ANDI, Yogyakarta. hlm. 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia. Jilid III (Terjemahan dari K. Heyne 1950). Jakarta. hlm. 1550.
Buletin Teknik Pertanian Vol. 10. Nomor 2, 2005
85
Anda mungkin juga menyukai
- Alkaloid Daun TempuyungDokumen7 halamanAlkaloid Daun TempuyungAyun Dwi AstutiBelum ada peringkat
- Fionnula Aprilia Siswoyo - 1920268 - Tugas Kromatografi KolomDokumen5 halamanFionnula Aprilia Siswoyo - 1920268 - Tugas Kromatografi Kolomintan aulBelum ada peringkat
- Kromatografi Lapis TipisDokumen3 halamanKromatografi Lapis TipisnisdinisdiBelum ada peringkat
- Bayu Santoso - 2C - Tugas Kimia Analisis OrganikDokumen23 halamanBayu Santoso - 2C - Tugas Kimia Analisis OrganikAries NoviantoBelum ada peringkat
- 09 Bab Iv Hasil Dan Pembahasan AntioksidanDokumen15 halaman09 Bab Iv Hasil Dan Pembahasan AntioksidanHanina F NurazminaBelum ada peringkat
- JURNAL Ta PDFDokumen6 halamanJURNAL Ta PDFAwandaFebrimawardhaniBelum ada peringkat
- Jurnal Fitokimia Ekstrak Binahong PDFDokumen23 halamanJurnal Fitokimia Ekstrak Binahong PDFDanang StwnBelum ada peringkat
- Laporan Uv VisDokumen21 halamanLaporan Uv VisMelda HasanovaBelum ada peringkat
- LAPORAN PRAKTIKUM Istikha NFDokumen10 halamanLAPORAN PRAKTIKUM Istikha NFIstikha NurfazhilahBelum ada peringkat
- Isolasi Dan Penetapan Kadar Alkaloid Ekstrak EtanolikDokumen13 halamanIsolasi Dan Penetapan Kadar Alkaloid Ekstrak Etanolikani kumarBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Fitokimia I Kelompok 6Dokumen13 halamanLaporan Praktikum Fitokimia I Kelompok 6Alva ChanBelum ada peringkat
- Fitokimia Bu MahyuniiDokumen15 halamanFitokimia Bu MahyuniiEndah SuryaniBelum ada peringkat
- Bab IV SkripsiDokumen7 halamanBab IV SkripsiNoviyanti KaiBelum ada peringkat
- Makalah KencurDokumen11 halamanMakalah KencurSukmaBelum ada peringkat
- Tanin LumayanDokumen8 halamanTanin LumayanNenden GoodlightBelum ada peringkat
- Alkaloid PPT - 1Dokumen17 halamanAlkaloid PPT - 1Wakhidah Umi SholikhahBelum ada peringkat
- MonoterpenDokumen12 halamanMonoterpenSALSABILLA NUR ZAHIRAHBelum ada peringkat
- 35-Article Text-759-1-10-20230829Dokumen15 halaman35-Article Text-759-1-10-20230829aprilianidevi367Belum ada peringkat
- Jurnal Daun MianaDokumen7 halamanJurnal Daun MianaMutiara NurfadillahBelum ada peringkat
- Isolasi Minyak Atsiri Dan Resin Serta Pemanfaatan Di Bidang KefarmasianDokumen10 halamanIsolasi Minyak Atsiri Dan Resin Serta Pemanfaatan Di Bidang KefarmasianAfdhonil Qomarul PBelum ada peringkat
- Laporan Ekstraksi FitokimDokumen29 halamanLaporan Ekstraksi Fitokimrima nurainiBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Ekstraksi Daun CengkehDokumen10 halamanLaporan Praktikum Ekstraksi Daun CengkehAnggi AulfBelum ada peringkat
- Isolasi Eugenol Dari Bunga Cenggkeh Dan Sintesis Eugenil AsetatDokumen5 halamanIsolasi Eugenol Dari Bunga Cenggkeh Dan Sintesis Eugenil AsetatreskydcBelum ada peringkat
- Ekstraksi SolventDokumen9 halamanEkstraksi SolventirenemitaBelum ada peringkat
- TPDokumen12 halamanTPDony Abram SimanjuntakBelum ada peringkat
- Ni Ketut Ermin - Review Jurnal Prak KobaDokumen9 halamanNi Ketut Ermin - Review Jurnal Prak KobaKetut ErminBelum ada peringkat
- Analisis Antioksidan Dari Berbagai Fraksi Daun Cokelat (TheobromaDokumen8 halamanAnalisis Antioksidan Dari Berbagai Fraksi Daun Cokelat (TheobromaindiyaniBelum ada peringkat
- AnalisisKualitatifdanKuantitatifKandunganKimiaDaunKumisKucingOrthosiphonaristatusBlumeMiqdariEkstrakHeksanAsetonEtanoldanAir PDFDokumen13 halamanAnalisisKualitatifdanKuantitatifKandunganKimiaDaunKumisKucingOrthosiphonaristatusBlumeMiqdariEkstrakHeksanAsetonEtanoldanAir PDFBerlianti Citra MaulidyaBelum ada peringkat
- Dwi Kumsia Aditiana 04011281621075Dokumen4 halamanDwi Kumsia Aditiana 04011281621075dindaamalaBelum ada peringkat
- Isolasi AlkaloidDokumen18 halamanIsolasi Alkaloidshiba meike indiraBelum ada peringkat
- Bab Iii. Metode Penelitian 3.1 Waktu Dan Tempat: Lieberman-Burchard, Quarsetin (CDokumen11 halamanBab Iii. Metode Penelitian 3.1 Waktu Dan Tempat: Lieberman-Burchard, Quarsetin (CNurlin AstutiBelum ada peringkat
- Analisis Kualitatifdan Kuantitatif Kandungan Kimia Daun Kumis Kucing Orthosiphonaristatus Blume Miqdari Ekstrak Heksan Aseton Etanoldan AirDokumen13 halamanAnalisis Kualitatifdan Kuantitatif Kandungan Kimia Daun Kumis Kucing Orthosiphonaristatus Blume Miqdari Ekstrak Heksan Aseton Etanoldan AirRita RakhmaBelum ada peringkat
- Kuis Kromatografi KolomDokumen8 halamanKuis Kromatografi KolomMegi YulistinBelum ada peringkat
- Ekstraksi Dan Isolasi TugasDokumen45 halamanEkstraksi Dan Isolasi TugasIsnaeni S. RahmadiBelum ada peringkat
- PDTK 2 - Percobaan 9 - Kelompok 17Dokumen19 halamanPDTK 2 - Percobaan 9 - Kelompok 17Zaidan NaufalBelum ada peringkat
- Makalah & Lap - Akhir Metode FitokimiaDokumen96 halamanMakalah & Lap - Akhir Metode FitokimiaMeta Riana SariBelum ada peringkat
- Fitokim PolifenolDokumen11 halamanFitokim PolifenolArizal GhazaliBelum ada peringkat
- Isolasi Daun BinahongDokumen24 halamanIsolasi Daun BinahongYaniBelum ada peringkat
- ZAKIYYAHDokumen13 halamanZAKIYYAHIndah lestari SubayirBelum ada peringkat
- UJI FITOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK DAUN RAMBUTAN (Nephelium Lappaceum) Dengan METODE DPPH (1,1-Diphenyl-2-Picryhidrazyl)Dokumen5 halamanUJI FITOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK DAUN RAMBUTAN (Nephelium Lappaceum) Dengan METODE DPPH (1,1-Diphenyl-2-Picryhidrazyl)Waode Cahaya Widya PutriBelum ada peringkat
- Kelompok 3 - Isolasi Dan Identifikasi Eugenol Dari Minyak CengkehDokumen7 halamanKelompok 3 - Isolasi Dan Identifikasi Eugenol Dari Minyak CengkehHilda fanesa putriBelum ada peringkat
- Nur Saidah Kholiliyah - Laporan Praktikum KIMOR 2Dokumen10 halamanNur Saidah Kholiliyah - Laporan Praktikum KIMOR 2Nur Saidah KholiliyahBelum ada peringkat
- Desmana Mei Yuliyati (R212110314) - UjianDokumen7 halamanDesmana Mei Yuliyati (R212110314) - UjianDesmanaBelum ada peringkat
- Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Antioksidan Dari Ekstrak Benalu Teh (Scurulla Oortiana) (Simanjuntak Et Al 2004)Dokumen6 halamanIsolasi Dan Identifikasi Senyawa Antioksidan Dari Ekstrak Benalu Teh (Scurulla Oortiana) (Simanjuntak Et Al 2004)Andal YakinudinBelum ada peringkat
- PEMANFAATAN EKSTRAK KULIT LABAN (Vitex Pubescens Vahl.) SEBAGAI BAHAN ANTI JAMURDokumen15 halamanPEMANFAATAN EKSTRAK KULIT LABAN (Vitex Pubescens Vahl.) SEBAGAI BAHAN ANTI JAMURDeny Kurniawan100% (1)
- Esculenta (L) Schott) MENGGUNAKAN METODE KLT-: (Colocasia DensitometriDokumen6 halamanEsculenta (L) Schott) MENGGUNAKAN METODE KLT-: (Colocasia DensitometriDimas rizky defadjriBelum ada peringkat
- Isolasi Dan Karakterisasi Terpenoid Dari Etil Asetat Kulit Batang Meranti KunyitDokumen12 halamanIsolasi Dan Karakterisasi Terpenoid Dari Etil Asetat Kulit Batang Meranti KunyitZuly Irawaty SitumorangBelum ada peringkat
- KLT SeskuiterpenDokumen5 halamanKLT SeskuiterpenJhohanis LeroBelum ada peringkat
- Maping KKG Kelompok 1Dokumen10 halamanMaping KKG Kelompok 1ANDIANY CAHYANTY TAHIRBelum ada peringkat
- Isolasi Dan Karakterisasi Terpena Dari Daun Croton MacrostachyusDokumen7 halamanIsolasi Dan Karakterisasi Terpena Dari Daun Croton MacrostachyusMuhammad Reza PratamaBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Antioksidan - Devina AuliaDokumen10 halamanLaporan Praktikum Antioksidan - Devina AuliaDevina AuliaBelum ada peringkat
- Dokumen 1Dokumen9 halamanDokumen 1syafirarsBelum ada peringkat
- FRAKSINASIDokumen2 halamanFRAKSINASISintya Dinna PranataBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Fitokimia I Kelompok Vi.Dokumen11 halamanLaporan Praktikum Fitokimia I Kelompok Vi.Alva ChanBelum ada peringkat
- Ekstraksi Daun Kumis KucingDokumen3 halamanEkstraksi Daun Kumis KucingYulia HastikaBelum ada peringkat
- Irvan Et Al 2015Dokumen6 halamanIrvan Et Al 2015Alam NuanzaBelum ada peringkat
- Laporan Perancangan ProsesDokumen19 halamanLaporan Perancangan ProsesAnnisa KramaBelum ada peringkat
- Haspeng Dan Pembahasan Triangle Dan Duo TrioDokumen5 halamanHaspeng Dan Pembahasan Triangle Dan Duo TrioAnnisa KramaBelum ada peringkat
- Mempelajari Tekstur MakananDokumen16 halamanMempelajari Tekstur MakananAnnisa Krama100% (1)
- Hasil Pengamatan Dan PembahasanDokumen6 halamanHasil Pengamatan Dan PembahasanAnnisa KramaBelum ada peringkat
- Latar Belakang Pengujian COD, BOD, Dan DODokumen2 halamanLatar Belakang Pengujian COD, BOD, Dan DOAnnisa KramaBelum ada peringkat
- Hasil Pengamatan Dan PembahasanDokumen9 halamanHasil Pengamatan Dan PembahasanAnnisa Krama100% (1)