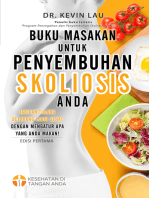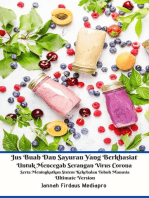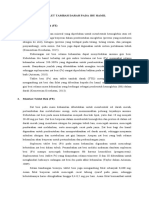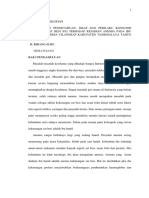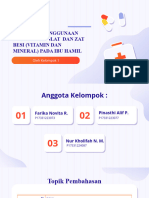Penjelasan Tablet Fe
Penjelasan Tablet Fe
Diunggah oleh
Fisya BethanJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Penjelasan Tablet Fe
Penjelasan Tablet Fe
Diunggah oleh
Fisya BethanHak Cipta:
Format Tersedia
1.
Pengertian Tablet Fe
Tablet Fe merupakan unsur kelumit (trace element) terpenting bagi manusia. Besi dengan konsentrasi
tinggi terdapat dalam sel darah merah, yaitu sebagai bagian dari molekul hemoglobin yang menyangkut
oksigen dari paruparu. Hemoglobin akan mengangkut oksigen ke selsel yang membutuhkannya untuk
metabolisme glukosa, lemak dan protein menjadi energi (ATP). Besi juga merupakan bagian dari sistem
enzim dan mioglobin, yaitu molekul yang mirip Hemoglobin yang terdapat di dalam selsel otot.
Mioglobin akan berkaitan dengan oksigen dan mengangkutnya melalui darah ke selsel otot. Mioglobin
yang berkaitan dengan oksigen inilah menyebabkan daging dan otototot menjadi berwarna merah. Di
samping sebagai komponen Hemoglobin dan mioglobin, besi juga merupakan komponen dari enzim
oksidase pemindah energi, yaitu: sitokrom paksidase, xanthine oksidase, suksinat dan dehidrogenase,
katalase dan peroksidas (NN, 2008).
Tablet Fe adalah sebuah nutrient esensial yang diperlukan oleh setiap manusia. Sebagai logam transisi
(nomor atom 26, berat atom 55,85), dapat berperan sebagai pembawa oksigen dan electron serta
katalisator untuk oksigenasi, hidroksilasi dan proses metabolik lainnya, melalui kemampuannya berubah
bentuk abtara Fero (Fe2+) dan fase oksidasi Fe3+ ( NN, 2008).
Tablet Fe adalah elemen biokatalitik yang paling penting dalam enzymologi manusia, dengan peran
utamanya dalam metabolism oksidatif, proliferasi dan pertumbuhan sel serta penyimpanan dan
transportasi oksigen ( NN, 2008).
2.Tujuan Pemberian Tablet Fe
Tujuan pemberian tablet Fe adalah untuk memperbaiki status besi ibu (NN, 2008).
3.Indikasi Pemberian Tablet Fe
Indikasi pemberian tablet Fe adalah ibu hamil, balita, anak usia sekolah, dan wanita usia subur termasuk
remaja putri dan pekerja wanita dengan kurangnya asupan zat besi.
4.Kontraindikasi Pemberian Tablet Fe
Kontraindikasi pemberian tablet Fe adalah jangan diberiakn pada pasien yang mengalami tranfusi darah
yang berulang atau anemia yang tidak disebabkan oleh kekurangan besi, pasien dengan ulcus peptikum,
hemokromatosis, colitis ulseratif, enteritis, serta penderita yang hipersensitif terhadap salah satu atau
kedua zat aktif.
5.Efek Samping Pemberian Tablet Fe
Efek samping dari pemberian tablet Fe adalah gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah,
kembung, konstipasi atau diare.
6.Konsumsi dan manfaat pemberian tablet Fe pada ibu hamil
Pemberian suplementasi besi untuk memperbaiki status gizi ibu yaitu dalam peningkatan Hb,
hematokrit, feriti serum dan saturasi transferin biasanya terjadi dalam 3 bulan. Tablet besi diberikan 30
mg besi perhari berlaku untuk semua wanita hamil tanpa memandang status besi oleh karena
manfaatnya bagi ibu dan anak. Dosis 30 mg perhari diberikan karena alasan efisiensi absorbs besi
menurun pada dosis yang lebih tinggi. Dengan dosis tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
besi 6 mg yang terabsorbsi perhari . Pada dosis yang lebih tinggi dapat menimbulkan efek samping
seperti diare, konstipasi, mual, nyeri dada seperti terbakar dan nyeri abdomen. Suplementasi tablet Fe
harus diberikan kepada trimester ke 2 dan 3, saat efisiensi absorbsi meningkat dan resiko terjadinya
mual muntah berkurang. Untuk di Indonesia, Depkes menyarankan pemberian tablet Fe pada semua
wabita hamil sekitar 60 mg per hari selama 90 hari.
Tablet Fe diperlukan untuk hemopoesis (pembentukan darah) dan juga diperlukan oleh berbagai enzim
sebagai factor penggiat. Tablet fe yang terdapat dalam enzim juga bermanfaat untuk mengangkut
elektro (sitokrom), untuk mengaktifkan oksigen (oksidase dan oksigenase) (Ulhaq, 2008).
Pada trimester pertama kehamilan, zat besi yang dibutuhkan sedikit karena tidak terjadi menstruasi dan
pertumbuhan janin masih lambat. Menginjak trimester kedua hingga ketiga , volume darah dalam tubuh
wanita akan meningkat sampai 35 %, ini ekuivalen dengan 450 mg zat besi untuk memproduksi sel-sel
darah merah. Sel darah merah harus mengankut oksigen lebih banyak untuk janin. Sedangkan saat
melahirkan, perlu tambahan besi 300-350 mg akibat kehilangan darah. Sampai saat melahirkan, wanita
hamil butuh besi sekitar 40 mg per hari atau dua kali lipat kebutuhan kondisi tidak hamil.
Mengingat dampak anemia dapat menurunkan kualitas sumber Daya manusia di Indonesia, maka perlu
penanggulangan kekurangan zat besi pada ibu hamil dengan segera. Oleh sebab itu pemerintah
Indonesia mulai menerapkan suatu program penambahan zat besi sekitar dua puluh tahun yang lalu.
Program ini didasarkan dengan harapan setiap ibu hamil secara teratur memeriksakan diri ke Puskesmas
atau Posyandu selama masa kehamilannya. Tablet Besi dibagikan oleh petugas kesehatan kepada ibu
hamil secara gratis ( Depkes, 2003).
Upaya penanggulangan anemia gizi diprioritaskan kepada kelompok rawan yaitu ibu hamil, balita, anak
usia sekolah, dan wanita usia subur termasuk remaja putri dan pekerja wanita. Selama ini upaya
penanggulangan anemia gizi difokuskan kepada sasaran ibu hamil dengan suplementasi tablet besi folat
(200 mg FeSO4 dan 0,25 mg asam folat) dengan memberikan setiap hari 1 tablet selama minimal 90 hari
berturut-turut ( Depkes, 2002).
Upaya-upaya dalam penanggulangan anemia gizi terutama pada wanita hamil telah dilaksanakan oleh
pemerintah. Salah satu caranya adalah melalui suplementasi tablet besi. Suplementasi tablet besi
dianggap merupakan cara yang efektif karena kandungan besinya padat dan dilengkapi dengan asam
folat yang sekaligus dapat mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan asam folat. Cara ini
juga efisien karena tablet besi harganya relatif murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat kelas bawah
serta mudah didapat (Depkes, 2002).
Menurut World Health Organization (2004), cara mengkonsumsi zat besi (Fe) adalah dalam
mengkonsumsi atau minum suplement zat besi (Fe) baik dalam hal waktu, frekuensi meminum tablet Fe
dan cara meminum suplement zat besi (Fe) yaitu sehari sekali dan diminum pada saat malam hari
karena efek dari meminum tablet Fe dapat menimbulkan rasa mual dan diminum dengan menggunakan
air jeruk agar penyerapan lebih maksimal serta dianjurkan untuk menghindarkan makan dan minum
yang menghambat penyerapan besi misalnya kopi serta teh. Suatu penelitian menunjukan bahwa wanita
hamil yang tidak minum pil besi mengalami penurunan ferritin (cadangan besi) cukup tajam sejak
minggu ke 12 usia kehamilan (Khomsan, 2003).
7.Zat Besi dalam Tubuh
Zat besi dalam tubuh terdiri dari dua bagian, yaitu yang fungsional dan yang reserve (simpanan). Zat besi
yang fungsional sebagian besar dalam bentuk Hemoglobin (Hb), sebagian kecil dalam bentuk myoglobin,
dan jumlah yang sangat kecil.
Zat besi yang ada dalam bentuk reserve tidak mempunyai fungsi fisiologi selain daripada sebagai buffer
yaitu menyediakan zat besi kalau dibutuhkan untuk kompartemen fungsional. Apabila zat besi cukup
dalam bentuk simpanan, maka kebutuhan kan eritropoiesis (pembentukan sel darah merah) dalam
sumsum tulang akan selalu terpenuhi. Dalam keadaan normal, jumlah zat besi dalam bentuk reserve ini
adalah kurang lebih seperempat dari total zat besi yang ada dalam tubuh. Zat besi yang disimpan
sebagai reserve ini, berbentuk feritin dan hemosiderin, terdapat dalam hati, limpa, dan sumsum tulang.
Pada keadaan tubuh memerlukan zat besi dalam jumlah banyak,misalnya pada anak yang sedang
tumbuh (balita), wanita menstruasi dan wanita hamil, jumlah reserve biasanya rendah.
Pada bayi, anak dan remaja yang mengalami masa pertumbuhan, maka kebutuhan zat besi untuk
pertumbuhan perlu ditambahkan kepada jumlah zat besi yang dikeluarkan lewat basal.
Dalam memenuhi kebutuhan akan zat gizi, dikenal dua istilah kecukupan (allowance) dan kebutuhan gizi
(requirement). Kecukupan menunjukkan kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi hampir semua
orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktifitas untuk mencapai derajat
kesehatan yang optimal. Sedangkan kebutuhan gizi menunjukkan banyaknya zat gizi minimal yang
diperlukan masing-masing individu untuk hidup sehat. Dalam kecukupan sudah dihitung faktor variasi
kebutuhan antar individu, sehingga kecukupan kecuali energi, setingkat dengan kebutuhan ditambah
dua kali simpangan baku. Dengan demikian kecukupan sudah mencakup lebih dari 97,5% populasi
(Muhilal et al, 1993).
8.Zat besi dalam makanan
Dalam makanan terdapat 2 macam zat besi yaitu besi heme dan besi non hem. Besi non hem
merupakan sumber utama zat besi dalam makanannya. Terdapat dalam semua jenis sayuran misalnya
sayuran hijau, kacang-kacangan, kentang dan sebagian dalam makanan hewani. Sedangkan besi hem
hampir semua terdapat dalam makanan hewani antara lain daging, ikan, ayam, hati dan organ-organ
lain.
9.Metabolisme zat besi
Untuk menjaga badan supaya tidak anemia, maka keseimbangan zat besi di dalam badan perlu
dipertahankan. Keseimbangan disini diartikan bahwa jumlah zat besi yang dikeluarkan dari badan sama
dengan jumlah besi yang diperoleh badan dari makanan. Suatu skema proses metabolisme zat besi
untuk mempertahankan keseimbangan zat besi di dalam badan. Setiap hari turn over zat besi ini
berjumlah 35 mg, tetapi tidak semuanya harus didapatkan dari makanan. Sebagian besar yaitu sebanyak
34 mg didapat dari penghancuran sel sel darah merah tua, yang kemudian disaring oleh tubuh untuk
dapat dipergunakan lagi oleh sumsum tulang untuk pembentukan sel-sel darah merah baru. Hanya 1 mg
zat besi dari penghancuran sel-sel darah merah tua yang dikeluarkan oleh tubuh melalui kulit, saluran
pencernaan dan air kencing. Jumlah zat besi yang hilang lewat jalur ini disebut sebagai kehilangan basal
(iron basal losses).
Total besi normal dalam tubuh, pada perempuan 2 g dan mencapai 6 g pada laki-laki. Jumlah tersebut
dibagi kedalam dua kelompok besar yaitu bagian fungsional dan cadangan. Kira-kira 80% besi fungsional
terdapat dalam hemoglobin; sisanya terdapat dalam mioglobin dan enzim yang mengandung besi
seperti katalase dan sitokrom. Cadangan besi berupa hemosiderin dan feritin mengandung kira-kira 15-
20% total besi tubuh. Wanita muda yang sehat memiliki cadangan besi sedikit lebih rendah
dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan tersebut lebih sering terjadi ganguan keseimbangan
besi dan lebih rentan kehilangan besi atau peningkatan kebutuhan karena menstruasi dan kehamilan
(Andrew, 1999).
Semua besi disimpan dalam bentuk feritin atau hemosiderin. Feritin merupakan kompleks besi-protein
yang esensial dan terdapat pada hampir semua jaringan terutama dalam hepar, limfa, sumsum tulang,
dan otot skletal. Dalam hepar, kebanyakan feritin disimpan dalam sel parenkim; sedangkan dalam
jaringan lain seperti limfa dan sumsum tulang, terutama disimpan dalam sel fagosit mononuklear. Besi
yang ada dalam hepatosit berasal dari transferin plasma, sedangakan besi yang berada dalam sel fagosit
mononuklear, termasuk sel Kupffer diperoleh dari pemecahan eritrosit. Didalam sel, feritin terletak
dalam sitoplasma dan lisosome, yang mana selaput protein feritin mengalami degradasi dan besi
beragregasi menjadi granul hemosiderin. Dengan pewarnaan sel yang biasa, hemosiderin tampak
sebagai granul berwarna kuning keemasan. Besi cepat bereaksi terhadap zat kimia sehingga ketika
hemosiderin dalam jaringan ditetesi dengan potassium ferrocyanide (prussian blue reaction), granula
berubah menjadi biru-hitam. Dengan cadangan besi normal, hanya sedikit hemosiderin yang ada dalam
tubuh, khususnya sel retikuloendotelial dalam sumsum tulang, limfa, dan hepar. Dalam sel dengan
jumlah besi berlebihan, kebanyakan besi disimpan dalam bentuk hemosiderin. (Hoffman, 2000;
Cuningam et al., 2001).
Feritin berada dalam sirkulasi dalam jumlah yang sangat kecil. Feritin plasma berasal dari cadangan besi
tubuh sehingga kadar feritin dapat dipakai sebagai indikator kecukupan cadangan besi tubuh. Dalam
keadaan defisiensi besi, kadar feritin serum selalu berada dibawah 12 mug/L, sebaliknya pada kondisi
besi yang berlebihan, nilai tertinggi mencapai 5000mug/L. Fungsi fisiologis yang penting dari cadangan
besi adalah siap dimobilisasi dalam keadaan kebutuhan besi meningkat, seperti pada keadaan setelah
perdarahan (Gary et al.,2000).
Besi diangkut dalam plasma oleh transferin yaitu suatu glikoprotein pengikat besi yang disintesis dalam
hepar. Pada orang normal, sekitar 33% transferin tersaturasi dengan besi dan kadarnya dalam serum
mencapai 120 mug/dl pada pria dan 100 mg/dl pada wanita. Dengan demikian, total kapasitas
pengikatan besi dalam serum berkisar antara 300-350 mg/dl. Fungsi utama transferin plasma ialah
menghantarkan besi kedalam sel, termasuk prekursor eritroid, dimana besi diperlukan untuk sintesis
hemoglobin. Eritrosit imatur memiliki afinitas yang tinggi terhadap reseptor transferin dan besi
dihantarkan ke eritroblast melalui endositosis yang diperantarai reseptor (Andrew, 1999; Gary et al.,
2000).
10.Faktor faktor yang mempengaruhi Penyerapan zat besi
Absorbsi zat besi dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu:
a.Kebutuhan tubuh akan besi, tubuh akan menyerap sebanyak yang dibutuhkan. Bila besi simpanan
berkurang, maka penyerapan besi akan meningkat.
b.Rendahnya asam klorida pada lambung (kondisi basa) dapat menurunkan penyerapan Asam klorida
akan mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+ yang lebih mudah diserap oleh mukosa usus
c.Adanya vitamin C gugus SH (sulfidril) dan asam amino sulfur dapat meningkatkan absorbsi karena
dapat mereduksi besi dalam bentuk ferri menjadi ferro. Vitamin C dapat meningkatkan absorbsi besi
dari makanan melalui pembentukan kompleks ferro askorbat. Kombinasi 200 mg asam askorbat dengan
garam besi dapat meningkatkan penyerapan besi sebesar 25 50 persen.
d.Kelebihan fosfat di dalam usus dapat menyebabkan terbentuknya kompleks besi fosfat yang tidak
dapat diserap.
e.Adanya filtrat juga akan menurunkan ketersediaan Fe
f.Protein hewani dapat meningkatkan penyerapan Fe
g.Fungsi usus yang terganggu, misalnya diare dapat menurunkan penyerapan Fe.
h.Penyakit infeksi juga dapat menurunkan penyerapan Fe
11.Proses Penyerapan zat besi
a.Besi yang terdapat di dalam bahan pangan, baik dalam bentuk Fe3+ atau Fe2+ mula-mula mengalami
proses pencernaan.
b.Di dalam lambung Fe3+ larut dalam asam lambung, kemudian diikat oleh gastroferin dan direduksi
menjadi Fe2+
c.Di dalam usus Fe2+ dioksidasi menjadi Fe3+. Fe3+ selanjutnya berikatan dengan apoferitin yang
kemudian ditransformasi menjadi feritin, membebaskan Fe2+ ke dalam plasma darah.
d.Di dalam plasma, Fe2+ dioksidasi menjadi Fe3+ dan berikatan dengan transferitin Transferitin
mengangkut Fe2+ ke dalam sumsum tulang untuk bergabung membentuk hemoglobin. Besi dalam
plasma ada dalam keseimbangan.
e.Transferrin mengangkut Fe2+ ke dalam tempat penyimpanan besi di dalam tubuh (hati, sumsum
tulang, limpa, sistem retikuloendotelial), kemudian dioksidasi menjadi Fe3+. Fe3+ ini bergabung dengan
apoferritin membentuk ferritin yang kemudian disimpan, besi yang terdapat pada plasma seimbang
dengan bentuk yang disimpan (NN, 2008).
Terdapat beberapa jenis makanan yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas besi yang dikatagorikan
sebagai pelancar dan penghambat zat besi. Golongan pelancar absorbsi antara lain hati sapi, daging sapi,
ayam, udang segar, kerang, telur ayam ras, kuning telur, susu sapi, kedele, tempe, tahu, daun kelor, sawi
kol, bayam, kangkung, pepaya, jeruk manis. Adapun golongan penghambat absorbsi antara lain Beras
ketan hitam tumbuk, jagung, katuk, daun singkong, daun pakis, buncis , jambu, teh, kopi.
Asupan normal zat besi biasanya tidak dapat menggantikan kehilangan zat besi karena perdarahan
kronik dan tubuh hanya memiliki sejumlah kecil cadangan zat besi sebagai akibatnya, kehilangan zat besi
harus digantikan dengan tambahan zat besi.
Janin yang sedang berkembang menggunakan zat besi, karena itu wanita hamil juga memerlukan
tambahan zat besi.
Makanan rata-rata mengandung sekitar 6 mgram zat besi setiap 1.000 kalori, sehingga rata-rata orang
mengkonsumsi zat besi sekitar 10-12 mgram/hari.
Sumber yang paling baik adalah daging, serat sayuran, fosfat, kulit padi (bekatul) dan antasid
mengurangi penyerapan zat besi dengan cara mengikatnya. Vitamin C merupakan satu-satunya unsur
makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Tubuh menyerap sekitar 1-2 mgram zat besi
dari makanan setiap harinya, yang secara kasar sama degnan jumlah zat besi yang dibuang dari tubuh
setiap harinya.
Anda mungkin juga menyukai
- Buku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!Dari EverandBuku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (4)
- Panduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanDari EverandPanduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)
- Referat Anemia Defisiensi BesiDokumen18 halamanReferat Anemia Defisiensi Besirendyjiwono100% (3)
- Mini Pro Tablet FeDokumen46 halamanMini Pro Tablet FegajBelum ada peringkat
- Jus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Ultimate VersionDari EverandJus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Ultimate VersionBelum ada peringkat
- PEMBERIAN FE Pada BumilDokumen9 halamanPEMBERIAN FE Pada BumilRachma Cii PoohmmeeuuhBelum ada peringkat
- Jurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Dari EverandJurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Penilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (7)
- Tumbuhan Herbal Yang Berkhasiat Mencegah Wabah Penyakit Edisi Bahasa Inggris 2021Dari EverandTumbuhan Herbal Yang Berkhasiat Mencegah Wabah Penyakit Edisi Bahasa Inggris 2021Belum ada peringkat
- Jus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Standar VersionDari EverandJus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Standar VersionPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Makalah Zat BesiDokumen10 halamanMakalah Zat Besiuhkty fauzyahBelum ada peringkat
- Metabolisme Zat BesiDokumen6 halamanMetabolisme Zat BesiSelvia RahayuBelum ada peringkat
- Metabolisme BesiDokumen13 halamanMetabolisme BesiAli Ahmad KhameiniBelum ada peringkat
- Sap Asam Folat Dan Zat BesiDokumen14 halamanSap Asam Folat Dan Zat BesiilmaratihBelum ada peringkat
- MINIPRODokumen46 halamanMINIPROAnonymous pXUAwBDvaVBelum ada peringkat
- Pemberian Dopamin Dan DobutaminDokumen3 halamanPemberian Dopamin Dan Dobutamintifano_arian9684Belum ada peringkat
- Pemberian Dopamin Dan DobutaminDokumen3 halamanPemberian Dopamin Dan Dobutamintifano_arian9684Belum ada peringkat
- Kelompok 6-Pengaruh Mineral Fe Terhadap ObatDokumen10 halamanKelompok 6-Pengaruh Mineral Fe Terhadap ObatSeptiBelum ada peringkat
- Pentingnya Mengkonsumsi Tablet Fe Pada Ibu Hamil - Septi Aulia Rani - d3 KebidananDokumen5 halamanPentingnya Mengkonsumsi Tablet Fe Pada Ibu Hamil - Septi Aulia Rani - d3 KebidananAmelia AryaniBelum ada peringkat
- Zat Besi11wordDokumen18 halamanZat Besi11wordtiachieveline82Belum ada peringkat
- Referat Anemia Defisiensi BesiDokumen28 halamanReferat Anemia Defisiensi BesiDewi Hanifa PrimanelzaBelum ada peringkat
- Kebutuhan Zat Besi Selama Masa KehamilanDokumen25 halamanKebutuhan Zat Besi Selama Masa KehamilanAidillah PutriBelum ada peringkat
- Zat BesiDokumen9 halamanZat BesiPratiwi Raissa WindianiBelum ada peringkat
- Zat Besi & Asam FolatDokumen12 halamanZat Besi & Asam FolatMradipta Arrya MBelum ada peringkat
- Materi Manfaat Tablet Tambah Darah Pada Ibu HamilDokumen4 halamanMateri Manfaat Tablet Tambah Darah Pada Ibu HamilVerytha SariBelum ada peringkat
- 178 501 1 PBDokumen27 halaman178 501 1 PBReani ZulfaBelum ada peringkat
- Teori Anemia - JurnalDokumen14 halamanTeori Anemia - Jurnaldamaris mangopangBelum ada peringkat
- Refleksi Kasus Nutrisi Pada Balita Dengan Anemia Defisiensi BesiDokumen6 halamanRefleksi Kasus Nutrisi Pada Balita Dengan Anemia Defisiensi BesiDiky Sukma WibawaBelum ada peringkat
- Pemberian Zat BesiDokumen35 halamanPemberian Zat Besieva hayati binti imanBelum ada peringkat
- Rama - 13201 - 10121001013 - 0008027801 - 0024016904 - 02Dokumen27 halamanRama - 13201 - 10121001013 - 0008027801 - 0024016904 - 02may siscaBelum ada peringkat
- Biskuit Daun KelorDokumen28 halamanBiskuit Daun KelorGitaMarthaVindiarti0% (1)
- Purple and Blue Gradients Aesthetic Y2K Group Project PresentationDokumen11 halamanPurple and Blue Gradients Aesthetic Y2K Group Project Presentationraisyusuf191Belum ada peringkat
- Modul TTDDokumen9 halamanModul TTDYuliana Suryanti100% (1)
- Bioavailabilitas MineralDokumen8 halamanBioavailabilitas MineralirfanBelum ada peringkat
- PKM Tentang Zat BesiDokumen21 halamanPKM Tentang Zat BesirisaBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen10 halamanBab IitasyaBelum ada peringkat
- Putri Rahma Nesa (19112254) - DikonversiDokumen7 halamanPutri Rahma Nesa (19112254) - DikonversiPutri rahma nesaBelum ada peringkat
- Makalah Rina Kel 6Dokumen27 halamanMakalah Rina Kel 6fitriyanadesi7Belum ada peringkat
- Proposal-Tablet Fe PD Ibu HamilDokumen23 halamanProposal-Tablet Fe PD Ibu Hamilindra_f04Belum ada peringkat
- Makalah Zat BesiDokumen10 halamanMakalah Zat BesiHanafi AhmadBelum ada peringkat
- Bioavailabilitas MineralDokumen16 halamanBioavailabilitas MineralGilman Ali RezaBelum ada peringkat
- Laporan Fe Kel 1Dokumen15 halamanLaporan Fe Kel 1Afra Rofiqoh RahmaBelum ada peringkat
- Kebutuhan Asam Folat Dan Fe Untuk Ibu HamilDokumen6 halamanKebutuhan Asam Folat Dan Fe Untuk Ibu HamiljabolbolBelum ada peringkat
- Penilaian Status Gizi Secara Biokimia Atau Laboratorium-1Dokumen32 halamanPenilaian Status Gizi Secara Biokimia Atau Laboratorium-1ella monicaBelum ada peringkat
- BAB II (FIN) Tablet Zat BesiDokumen22 halamanBAB II (FIN) Tablet Zat BesiDofi Pebriadi100% (1)
- Metabolisme Besi Saat HamilDokumen8 halamanMetabolisme Besi Saat HamilRESSABelum ada peringkat
- Metabolisme BesiDokumen29 halamanMetabolisme BesiAlFi KamaliaBelum ada peringkat
- Anemia Defisiensi Besi FixDokumen14 halamanAnemia Defisiensi Besi FixDebby SeresthiaBelum ada peringkat
- Anemia Karena Kekurangan Zat BesiDokumen47 halamanAnemia Karena Kekurangan Zat BesiLitha Afrianty HarianjaBelum ada peringkat
- Makalah Mata Kuliah Fortifikasi Dan Formulasi GiziDokumen17 halamanMakalah Mata Kuliah Fortifikasi Dan Formulasi GiziSiti Nurul Faizatus SholikhaBelum ada peringkat
- Alcoholism Treatment Drugs Breakthrough - by SlidesgoDokumen18 halamanAlcoholism Treatment Drugs Breakthrough - by SlidesgoPINASTHI ALIF PRAFASASTIBelum ada peringkat
- KasusDokumen7 halamanKasusAulia YuliartiBelum ada peringkat
- Kebutuhan Mineral Dalam Tubuh KitaDokumen4 halamanKebutuhan Mineral Dalam Tubuh KitaLilik Moo Izzah100% (1)
- Anemia Gizi BesiDokumen11 halamanAnemia Gizi BesiuflafaBelum ada peringkat
- Anemia Defisiensi Besi Pada Bayi Dan Anak PDFDokumen17 halamanAnemia Defisiensi Besi Pada Bayi Dan Anak PDFEka Ariasyah33% (3)
- Referat AdbDokumen17 halamanReferat AdbTria BrieBelum ada peringkat
- BesiDokumen9 halamanBesiwinidwiyuniarti34Belum ada peringkat
- Homeostasis BesiDokumen12 halamanHomeostasis BesiRatu Missa QBelum ada peringkat
- Fe, ZN, SeDokumen23 halamanFe, ZN, Setasyafebyona362Belum ada peringkat
- Anemia Defisiensi BesiDokumen15 halamanAnemia Defisiensi BesiWorker DozerBelum ada peringkat
- BAB II PurwantiDokumen13 halamanBAB II PurwantiPurwanti santosoBelum ada peringkat
- Penjelasan Tablet FeDokumen6 halamanPenjelasan Tablet Fetifano_arian9684Belum ada peringkat
- Kolestasis Pada BayiDokumen5 halamanKolestasis Pada Bayitifano_arian9684Belum ada peringkat
- Sinusitis Pada AnakDokumen2 halamanSinusitis Pada Anaktifano_arian9684100% (1)
- Amyotrophic Lateral SclerosisDokumen5 halamanAmyotrophic Lateral Sclerosistifano_arian9684Belum ada peringkat
- Case Tifano MiopiaDokumen32 halamanCase Tifano Miopiatifano_arian9684Belum ada peringkat