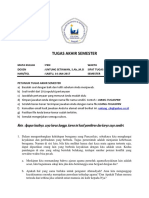Agama Sebagai Faktor Pemersatu
Diunggah oleh
Alie_Akbar63Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Agama Sebagai Faktor Pemersatu
Diunggah oleh
Alie_Akbar63Hak Cipta:
Format Tersedia
Agama Sebagai Faktor Pemersatu?
Penngantar
Pembahasan tentang agama sebagai faktor pemersatu sebenarnya menunjukkan
adanya gejala-gejala sebaliknya, yaitu agama kelihatan seolah-olah telah menjadi
faktor pemecah di negeri kita. Mungkin agama memang mempunyai potensi
memecah-belah.Sepanjang sejarah, agama sering kali menjadi sebab atau dalih
timbulnya peperangan.Yang kita kenal sebagai Perang Salib merupakan kasus
yang menonjol, yang terdiri atas serangkaian peperangan selama dua abad, dari
menjelang akhir abad ke-11 hingga menjelang akhir abad ke-13. Tetapi
peperangan itu sebenarnya juga melibatkan kepentingan politik dan ekonomi
negara-negara Eropa. Juga dalam perkembangan politik internasional masa kini,
sentimen keagamaan sering mencuat dan dimengerti secara berlebihan sebagai
faktor paling menentukan dalam berbagai konflik seperti di Sudan, Lebanon,
Aljazair, dan di Irlandia Utara, serta konflik etnis di bekas negara-negara
komunis di Eropa Timur sejak akhir Perang Dingin seperti di Bosnia.
Di negeri kita sendiri, akhir-akhir ini mencuat aksi-aksi kebringasan massal,yang
salah atau benar seringkali dikaitkan dengan sentimen keagamaan, terutama
dengan dirusaknya tempat-tempat ibadat. Gejala-gejala seperti itu membuat
pembicaraan tentang agama sebagai faktor pemersatu ataupun peranannya dalam
perdamaian kedengaran ironis dan mengandung kontradiksi, meskipun yang
sebenarnya terjadi dalam kasus-kasus tadi adalah perilaku orang-orang beragama
yang tidak sesuai dengan cita-cita dan komitmen agamanya pada perdamaian.
Dalam konteks Indonesia, persatuan, perdamaian, dan kerjasama antar berbagai
kelompok agama merupakan suatu keharusan, karena dengan membentuk negara
Indonesia merdeka sebagai negara-bangsa, kita semua telah bertekad untuk
hidup bersama terus sebagai suatu bangsa. Di sinilah letak makna pemahaman
dan penghayatan wawasan kebangsaan Indonesia.
Sebenarnya, secara konseptual, masalah kebangsaan Indonesia telah selesai.
Tetapi sebagai suatu cita-cita, persatuan bangsa, dan dengan demikian
penghayatan wawasan kebangsaan harus diperjuangkan terus-menerus. Ia tidak
dapat taken for granted.
Salah satu kelalaian banyak orang dalam masalah pembinaan persatuan bangsa,
dan dengan demikian wawasan kebangsaan, adalah bahwa konsep kebangsaan
kita (kebangsaan Indonesia) telah dibina sebagai suatu konsep politik, bukan
konsep etnis, rasial, keagamaan, kultural, linguistik, atau ikatan-ikatan sektarian
atau primordial lainnya. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia dibentuk dari
bangsa-bangsa dalam arti sempit (Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Ambon,
dsb.) terutama oleh kehendak menjadi satu bangsa baru, untuk hidup bersama,
senasib sepenanggungan dalam suatu bangsa baru itu, yaitu bangsa Indonesia,
sehingga Indonesia merdeka yang hendak didirikan akan merupakan negara-
bangsa, dalam wilayah tanah air Indonesia, yang sebelumnya merupakan daerah
jajahan Belanda, yaitu Hindia Belanda.
Pemikiran dan aspirasi politik itulah yang merupakan faktor utama pemersatu
bangsa Indonesia. Faktor lain adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional,
yang merupakan konsensus atau kompromi antara bahasa berbagai bangsa
dalam pengertian sempit tadi. Dan faktor ketiga adalah tanah air Indonesia dalam
batas-batas seperti dikatakan di atas. Ketiga faktor pemersatu inilah yang
dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, dengan
ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi negara, sebenarnya sila pertama
Ketuhanan Yang Maha Esa mempersatukan berbagai agama yang hidup dalam
masyarakat dalam kebangsaan Indonesia.
Implikasi dari konsep kebangsaan seperti itu adalah bahwa tiada kelompok
dalam bangsa Indonesia, baik kelompok besar atau mayoritas maupun
kelompok kecil atau minoritas, entah dalam pengertian etnis, ras, keagamaan,
bahasa, ataupun budaya, yang mempunyai kedudukan istimewa atau menikmati
hak-hak istimewa. Semua orang dan semua kelompok, mempunyai hak dan
kewajiban atau komitmen yang sama sebagai warga negara dan berkedudukan
sama (equal) di depan hukum
Tetapi pengalaman kita menunjukkan, bahwa faktor-faktor pemersatu bangsa itu
nampaknya belum cukup kuat untuk mempertahankan dan memperkokoh
persatuan bangsa. Masalahnya sekarang bagaimana agama, yang sebenarnya
mempunyai potensi sebagai faktor pemecah-belah itu justru dapat menjadi
sdalah satu faktor pemersatu, dalam arti mendukung persatuan bangsa Indonesia,
dan dengan demikian wawasan kebangsaan Indonesia. Kita dapat berbagi
pandangan tentang komitmen kita masing-masing pada persatuan bangsa. Dalam
proses itu, kita dapat mengembangkan pemahaman dan penghayatan yang sama
tentang persatuan bangsa. Jika demikian kita dapat menemukan dan
memantapkan titik temu, kendati perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam hal
iman dan kepercayaan, maupun perbedaan latar belakang etnis, ras, bahasa dan
budaya.
Syarat utama bagi terpeliharanya persatuan bangsa adalah keadilan. Kita tidak
dapat berbicara tentang persatuan dan juga integrasi bangsa tanpa membicarakan
masalah pemerataan dan kebersamaan, atau masalah yang lebih luas, yaitu
masalah keadilan.
Sebab itu inti masalahnya adalah, bagaimana kelompok-kelompok agama dapat
bekerjasama dalam perjuangan memerangi ketidakadilan, dan dengan demikian
menegakkan keadilan., di samping masalah-masalah bersama lainnya, seperti
masalah lingkungan hidup dan keterbelakangan. Masalah-masalah itu jelas
melampaui batas-batas keagamaan, etnis, rasial, bahasa ataupun budaya.
Keadilan sosial merupakan salah satu masalah bersama seluruh masyarakat, jadi
juga bagi semua golongan agama. Masalah keadilan sosial jugalah yang
seringkali menjadi sumber ketidakstabilan yang dapat berkembang seakan-akan
menjadi masalah agama.
Tetapi hal itu terjadi mungkin karena kita umat beragama kurang menyadari,
memahami dan menghayati komitmen bersama kita pada cita-cita kesejahteraan
umum, kepada sesama kita, justru sebagai penjabaran iman, kepercayaan, cinta
kasih, dan pengabdian kita kepada Tuhan, sekalipun melalui agama yang
berbeda-beda. Komitmen bersama ini yang perlu kita temukan dan kita
mantapkan. Dapat diharapkan bahwa sekurang-kurangnya dalam pemikiran-
pemikiran tentang keterlibatan atau partisipasi dalam kehidupan politik, akan
kita dapatkan titik temu antar umat berbagai agama. Dengan demikian bukan
saja kita dapat membina saling pengertian dan toleransi lebih besar, tetapi juga
kesadaran yang lebih tinggi akan adanya masalah-masalah bersama yang
dihadapi umat berbagai agama, sehingga kita dapat menggalang usaha bersama
untuk mengatasi masalah-masalah bersama itu demi kepentingan bersama pula.
Atas dasar pemikiran itu, pembahasan di sini akan meninjau kaitan antara
persatuan bangsa dan keadilan, dan peranan agama dalam negara Pancasila.
Karena penulis adalah pemeluk agama Kristen-Katolik, tinjauan itu akan
dilakukan dari sudut pemahamannya pribadi tentang hal itu sebagai orang
Katolik.
Persatuan Bangsa & Keadilan Sosial
Salah satu masalah mendesak saat ini adalah pengentasan kemiskinan. Kita juga
diajak untuk selalu memihak, membela, dan memperjuangkan mereka yang
miskin, lemah, dan tertindas, sebagaimana Yesus juga demikian. Dengan
demikian, kesejahteraan akan lebih merata, semuanya akan kopen, karena
mereka yang tidak miskin dapat ngopenidirinya sendiri.
Tetapi sebagai masalah kemasyarakatan, yang harus mendapat perhatian lebih
besar dan memperoleh prioritas lebih tinggi sebenarnya buikan kemiskinan,
melainkan kesenjangan atau ketidakadilan. Memang, kemiskinan itu sendiri
menyakitkan, bahkan kalaupun secara merata semua orang miskin. Tetapi
kemiskinan akan lebih menyakitkan, jika ditengah kemiskinan itu terdapat
kekayaan yang dinikmati dan dipamerkan secara menyolok hanya oleh
sekelompok kecil anggota masyarakat.
Meskipun demikian, dalam berbicara tentang kesenjangan atau ketidakdilan,
orang seringkali terlalu menekankan jurang antara kaya dan miskin, khususnya
dalam pengertian kesejahteraan materiil (ekonomi), baik pada tingkat
perorangan, antar kelompok, maupun antar daerah. Ketidakadilan dalam bidang
itu memang lebih nyata kelihatan daripada ketidakadilan dalam bidang-bidang
lain. Sebenarnya jurang kaya-miskin hanya merupakan salah satu bentuk
kesenjangan, yang juga meliputi bidang-bidang lain, termasuk diskriminasi, atau
perlakuan yang tidak sama/adil (unequal treatment), apa pun alasannya, dan
yang dapat juga diderita oleh mereka yang tidak miskin.
Ketidakadilan, bukan kemiskinan per se, merupakan sumber ancaman terhadap
perdamaian dan stabilitas. Komunisme lahir juga bukan karena kemiskinan itu
sendiri, tetapi karena ketidakadilan dan penindasan, meskipun pendekatannya
akhirnya hampir semata-mata dari segi materiil.
Secara umum keadilan dapat dimengerti sebagai suatu prinsip, norma, atau
sikap, yang menuntut persamaan. Dalam pengertian ini keadilan sama dengan
asas demokrasi sebagai suatu cita-cita. Sebab itu demokrasi dan keadilan saling
berkaitan, bahkan mungkin dapat dikatakan merupakan suatu kesatuan yang tak
terpisahkan. Demokrasi menuntut persamaan atau keadilan, dan keadilan dalam
masyarakat atau keadilan sosial hanya dapat diwujudkan secara lebih baik dalam
sistem demokrasi.
Tuntutan atas persamaan itu ialah agar hak setiap orang dihormati dan semua
manusia diperlakukan secara sama (equal). Ini berlaku pada kepentingan
manusia dalam semua hidang kehidupan, ya dalam bidang hukum, sosial, politik,
hudaya, maupun ekonomi. Asas ini bertolak dari keyakinan kita bahwa semua
manusia oleh Tuhan diciptakan sama di hadapan-Nya. Sebab itu asas keadilan
menolak segala bentuk diskriminasi, apa pun dasarnya. Dan sebab itu pula,
penerapan asas keadilan secara konsekuen membantu integrasi dan persatuan
bangsa. Seseorang atau sesuatu kelompok bersedia diajak bersatu dan
berintegrasi - apapun maknanya - hanya jika dia atau mereka merasa
diperlakukan secara adil, jika mereka tidak merasa menderila sesualu bentuk
kelidakadilan yang menyangkut kepentingannya.
Tetapi keadilan merupakan suatu asas atau tuntutan yang abstrak. Sebab itu,
usaha menegakkan keadilan ditempuh terutama melalui usaha memerangi
ketidakadilan. Dan karena ketidakadilan dalam bidang sosial-ekonomi lebih
nyata kelihatan, bidang itulah yang biasanya mendapat perhatian utama. Wujud
keadilan dalam masyarakat inilah yang biasa kita mengerti sebagai keadilan
sosial.
Tetapi bahkan dalam pengertian itu pun, penekanan pada usaha pengentasan
kemiskinan sebenarnya belum mengenai sasaran, karena kesenjangan atau
ketidakadilan dalam bidang sosial-ekonomi mempunyai dua dimensi, yaitu
kemiskinan dan kekayaan. Sebab itu, pendekatan yang ditempuh untuk
mengatasinya seharusnya juga berdimensi ganda. Mengentaskan kemiskinan
saja, yang sudah cukup berat, tidak akan berhasil mengatasi kesenjangan tanpa
menyentuh kekayaan, yaitu tanpa membatasi akumulasi dan pameran kekayaan.
Satu cara yang efektif untuk membatasi kekayaan adalah peraturan perpajakan
dengan enforcement yang tegas dan konsisten untuk tujuan itu.
Menanggulangi ketidakadilan, termasuk pengentasan kemiskinan, adalah tugas
negara. Ini memang sudah diusahakan, khususnya melalui program IDT. Tetapi
kebijakan itu masih memberi kesan usaha kosmetik dan tambal-sulam.Yang
diperlukan adalah usaha yang komprehensif melalui perundangan, terutama
penjabaran pasal 34 UUD, yang belum pernah disentuh.
Dapat dimengerti bahwa negara belum mampu menanggulangi masalah itu
secara memuaskan ke arah pengembangan suatu welfare state (negara
kesejahteraan) seperti di Inggris dan negara-negara Skandinavia, misalnya, yang
menyediakan jaminan sosial (social security benefit) untuk kesehatan,
pendidikan, pengangguran, dan usia lanjut. Tetapi perlu mulai diletakkan dasar-
dasarnya untuk tujuan seperti itu dalam jangka panjang. Usaha-usaha insidentil,
melalui yayasan-yayasan swasta yang mencanangkan program orang tua asuh
atau beasiswa, meskipun dengan tujuan-tujuan luhur, kurang efektif.
Begitu pula halnya dengan pendekatan melalui himbauan-himbauan kepada para
pengusaha dan konglomerat kaya, kurang mengena, apalagi mereka itu konon
sudah sering ditodong seperti sapi perahan untuk membantu membiayai
berbagai program pemerintah juga. Kepentingan utama para pengusaha adalah
laba atau keuntungan, kalau tidak usahanya memang akan bangkrut. Jadi
perahan itu akhirnya akan dibebankan pada para pekerja dan konsumen.
Memang ideal jika para pengusaha juga dermawan secara sukarela tanpa
himbauan, yang praktis seringkali sama saja dengan paksaan. Tetapi tidak
adil mengharapkan mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya merupakan
tugas negara. Cukup jika dengan pengawasan efektif mereka mentaati
perundangan dan peraturan yang adil yang mengatur hubungan perburuhan,
kesejahteraan pekerja, dan perpajakan yang bertujuan menegakkan keadilan.
Negeri ini terlalu kaya untuk membiarkan kemelaratan yang menusuk hati dan
rasa keadilan. Tetapi terkesan kekayaan negeri ini dinikmati dan dipamerkan
secara berlebihan oleh sekelompok kecil, terutama mereka yang terkesan
diperlakukan secara instimewa dengan penggunaan kekuasaan negara. Bung
Hatta pernah berkata beberapa puluh tahun yang lalu bahwa negara . . . belum
menjalankan keadilan sosial, apabila fakir miskin masih berkeliaran di tengah
jalan, dan anak-anak . . . terlantar hidupnya.
Di samping stabilitas, juga persatuan bangsa hanya bisa dipelihara dan
diperkokoh atas dasar keadilan, bukan dengan himbauan, penyeragaman,
indoktrinasi dan ancaman. Meningkatnya sektarianisme dalam bentuk sentimen
kesukuan, rasial, keagamaan, dsb., yang sering menandai kebringasan dalam
masyarakat, mungkin disebabkan terutama oleh persepsi semakin meningkatnya
ketidakdilan dalam berbagai manifestasinya.
Jika benar, semua itu merupakan petunjuk, bahwa sistem politik kita tidak
berfungsisebagaimana mestinya. The state does not deliver the goods. Agar
orang tidak merasa terpaksa mencari dan memaksakan sistem alternatif melalui
jalan-jalan yang destruktif dan kurang damai, terutama dengan mempergunakan
ikatan primordial, khususnya keagaman, pembaruan politik memang
mendesak.
Agama & Negara Pancasila
Pada umumnya sikap kita masih ambivalen dalam masalah kedudukan agama
dalam Negara Pancasila, atau hubungan antara agama dan ideologi Pancasila.
Apakah Negara Pancasila merupakan negara agama, atau negara sekuler?
Apakah dalam Negara Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang
Maha Esa, setiap warga negara harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa?
Apakah setiap warga negara harus beragama, artinya percaya kepada Tuhan
Yang Maha Esa melalui sesuatu agama? Dan apakah orang hanya boleh
memeluk salah satu agama yang diakui negara?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya dihindari, atau tidak diberi jawaban
yang tegas dan jelas. Pertanyaan pertama, misalnya, sering dijawab dengan
mengatakan bahwa Negara Pancasila bukan negara agama, tetapi juga bukan
negara sekuler.2 Atau pertanyaan seperti itu dapat juga diberi jawaban secara
yuridis formal, misalnya bahwa orang hanya boleh memeluk salah satu agama
yang diakui, karena memang demikian peraturannya. Jarang sekali terdengar
orang mempersoalkan, mengapa demikian, mengapa peraturan seperti itu dibuat,
apa dasar pertimbangannya, dsb.
Dalam pengertian saya, agama tidak berpengaruh atau berperanan secara
langsung dalam Negara Pancasila, melainkan secara tidak langsung melalui
peranan umat beragama dalam Negara Pancasila, yaitu peranannya dalam
kehidupan bermasyarakat dan bemegara. Agama merupakan pedoman hidup
pemeluknya. Ia memberi kepada pemeluknya pedoman atau petunjuk yang me-
nyangkut segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan bemegara, atau
kehidupan politik. Oleh sebab itu berbicara tentang posisi agama dalam Negara
Pancasila, hubungan agama dan ideologi Pancasila, atau peranan agama dalam
Negara Pancasila, kita juga berbicara tentang peranan atau partisipasi umat
beragama dalam kehidupan politik.
Kebebasan Beragama
Berbicara tentang peranan, partisipasi, atau keterlibatan "umat beragama" dalam
politik, sebenarnya secara implisit kita mengakui adanya orang-orang yang tidak
beragama, yang juga berpartisipasi atau terlibat dalam kehidupan politik. Kalau
tidak, istilah umat beragama" akan kehilangan artinya sama sekali, sekurang-
kurangnya sepanjang hal itu menyangkut masalah partisipasi dalam kehidupan
politik.
Di negeri ini telah menjadi semacam conventional wisdom, bahkan semacam
hukum yang tidak tertulis, seakan-akan setiap orang harus beragama. Dalam
KTP, misalnya, orang diharapkan mengisi kolom "agama", dan orang takut jika
tidak mengisinya, atau mengisi "tidak beragama", dia akan dituduh "atheis," "ko-
munis", "anggota PKI", atau mungkin "tidak Pancasilais", atau tuduhan-tuduhan
lain yang serba negatif.
Kasus yang paling menyolok adalah ketentuan UndangUndang Perkawinan,
khususnya Bab III, pasal 10, ayat (2) yang mengatakan bahwa "Tatacara
perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu". Ketentuan ini implisit berarti bahwa orang tidak beragama
atau tidak berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, atau memeluk agama di
luar kelima agama yang diakui, tidak bisa kawin di negeri ini. Atau orang harus
berbohong! Dengan kata lain, undang-undang itu telah menanamkan benih
kemunafikan. Yang saya maksudkan adalah bahwa percaya atau tidak dalam
batinnya, seseorang harus mengaku memeluk sesuatu agama. Kalau kebetulan
dia memang meyakini agama yang diakunya, dia jujur, tidak munafik. Tetapi
jika dia kebetulan tidak percaya agama itu, atau bahkan tidak percaya pada
Tuhan YME, dia harus pura-pura. Disini dia munafik. Sebenamya kemunafikan
merupakan salah satu kecenderungan sifat manusla biasa yang negatif, tetapi
yang harus kita coba kikis, bukannya didorong, meskipun tidak langsung,
melalui keharusan beragama atau percaya pada Tuhan YME, betapa pun baik
intensinya.
Ketentuan dalam UU Perkawinan itu bertentangan dengan Ketetapam MPR
Nomor II/MPR/1968 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(Ekaprasetya Pancakarsa). Meskipun saya menentang penataran P-4 yang
menjadt keputusan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
beribadat menurut agamanya dan Ketetapan MPR itu, penjelasan atas Bab II
angka 1 tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hubungan ini pantas
dikutip sebagai berikut:
Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut
pada bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama
atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu
berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan
memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan
menganutnya.
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemer-
dekaan tiap-tiap kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah
merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak
asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung
bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau
bukan pemberian golongan.
Undang-undang Perkawinan itu juga semakin mempersulit, kalau tidak malahan
tidak memungkinkan sama sekali, perkawinan campur antar agama. Saya juga
tidak yakin, apakah semua agama mengatur cara-cara perkawinan secara
khusus."Kewajiban" atau keharusan beragama atau berkepercayaan itu pun
masih dibatasi lagi, yaitu orang hanya dapat memeluk salah satu agama yang
diakui. Tentu dapat dipersoalkan, apa dasar pengakuan itu? Jika pengakuan itu
didasarkan pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, me-
ngapa agama Yahudi, yang paling dulu mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa
(monotheis), tidak diakui di negeri ini? Apakah pengakuan itu dengan demikian
didasarkan pada penimbangan-pertimbangan politik, misalnya karena kita tidak
mengakui Israel? Atau karena di negeri ini agama Yahudi memang tidak ada
pengikutya?
Sebenarnya agama tidak memerlukan pengakuan resmi atau restu dari negara.
Negara tidak mempunyai hak, wewenang, atau kompetensi untuk menentukan
sesuatu bentuk worship atau kepercayaan itu sebagai agama atau bukan. Mutatis
mutandis, negara juga tidak berhak menilai apakah sesuatu aliran agama itu
"sesat", tidak sesuai atau benentangan dengan the mainstream, yaitu yang
dianggap aliran yang "baku".
Dalam hal kebenaran Ilahi, siapa berhak menentukan mainstream itu? Hak
sepeni itu secara implisit mengklaim monopoli atas kebenaran, dan hendak
memaksakannya pada orang lain. Selama ini hanya kaum komunis atau para
penganut ideologi tenutup lainnya saja yang mengklaim monopoli atas seluruh
kebenaran.
Jika negara diberi hak atau wewenang untuk memberikan pengakuan itu, secara
logis negara juga berhak mencabut atau menarik kembali pengakuan itu, apa pun
alasannya. Padahal memeluk dan menganut sesuatu agama merupakan salah satu
perwujudan hak asasi manusia. Dan manusia memiliki hak asasi karena ia lahir
dan diciptakan Tuhan sebagai manusia. Ia melekat secara inheren dan tak
terpisahkan (inalienable) dalam jati diri manusia sebagai manusia. Sebab itu
hanya Tuhan dapat mencabutnya. Tetap menjadi tugas dan kewajiban Negara
untuk "mengayomi" atau melindungi kebebasan dalam kehidupan beragama, dan
menciptakan iklim yang sehat yang memungkinkan dan mendukung
dilaksanakannya kebebasan beragama dalam suasana kerukunan, saling
pengertian, saling menghormati, dan bahkan kerja sama.
Kembali pada masalah aliran "sesat", kalaupun sesuatu sekte, gerakan atau aliran
keagamaan memang "sesat", jika perlu negara dapat dan mungkin justru harus
bertindak, bukan terhadap "kesesatan" keagamaan itu an sich, tetapi, kalau ada,
terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum negara yang menyangkut
ketertiban umum, khususnya hukum pidana, seperti misalnya perkawinan anak-
anak di bawah umur atau pembunuhan massal sebagai ritual yang dituntut oleh
persyaratan agama itu. Contoh-contoh kasus seperti itu adalah apa yang pernah
terjadi di Guyana tahun 1970-an dengan suatu sekte fanatik di bawah pimpinan
Jim Jones, aliran serupa di bawah pimpinan David Koresh di Waco, Texas,
Amerika Serikat tahun 1994, dan para penganut aliran Family of Love di
Argentina, yang mengingatkan kita pada aliran Children of Goddi California
tahun 1960-an.
Peringatan yang pernah diberikan oleh Presiden Soeharto dalam hal ini sangat
tepat, dan pantas dikutip di sini. Dalam sambutannya pada pembukaan rapat
kerja Departemen Agama di Istana Negara,Jakarta, tanggal 22 Maret 1994,
antara lain Presiden berkata, bahwa:
Seluruh jajaran Departemen Agama harus terus berusaha meng-
hidup-hidupkan semangat kebersamaan di antara umat berbagai
agama, tanpa pembedaan satu sama lain. sesuai dengan
kedudukan dan fungsinya, seluruh jajaran Departemen Agama
hendaknya menghindari keterlibatan dalam masalah-masalah
intern keagamaan dari masing-masing umat beragama; baik
berkenaan dengan pemahaman, penafsiran maupun pengamalan
ajaran agama.
Hal-hal itu merupakan hak otonom masing-masing umat ber-
agama. Hal ini penting disadari, dalam usaha kita menetapkan
hubungan antara agama dan negara yang sehat dan segar di masa-
masa yang akan datang.
Kekhawatiran, apalagi tuduhan seakan-akan timbulnya sesuatu atau berbagai
aliran agama yang tidak sesuai dengan apa yang dianggap atau diakui
sebagai mainstream itu mengancam persatuan umat, bahkan persatuan bangsa,
sebenarnya tidak tepat dan tidak cukup beralasan. Kalau pun terdapat ancaman
terhadap persatuan, pihak yang menuduh kesesatan harus memikul tanggung
jawab lebih besar atas timbulnya kekhawatiran semacam itu atau ancaman
perpecahan, karena pihak itu secara implisit mengklaim monopoli atas
kebenaran dan hendak memaksakannya pada orang-orang lain.
Dalam sambutannya pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana
Negara, Jakarta, tanggal 19 Agustus 1994, Presiden Soeharto mengingatkan,
agar perbedaan agama, aliran dan pemahaman keagamaan tidak sampai
membuat bangsa ini terpecah-belah dan bermusuhan satu sama lain, sebab
menurut pengalaman sejarah perkembangan agama-agama tidak jarang
pertentangan berbagai aliran dan pemahaman di antara umat seagama bisa jauh
lebih sengit dan lebih parah dibandingkan dengan perbedaan agama.
Sebenarnya, pandangan pemerintah, dalam hal ini khususnya Presiden Soeharto,
hingga sekarang konsisten tentang hal itu. Sudah hampir lima-belas tahun yang
lalu, ketika menyambut Pembukaan Sidang Raya ke IX Dewan Gereja-gereja di
Indonesia (DGI) pada tanggal 19Juli 1980 di Manado, Presiden mengatakan,
antara lain, bahwa:
... Pemerintah tidak ingin mencampuri urusan intern masing--
masing agama ataupun lembaga-lembaga agama. Tetapi adalah
kewajiban Pemerintah yang bertanggung jawab agar dalam
negara . . . yang berdasarkan Pancasila ini dapat kita jaga
keutuhan, kerukunan dan keserasian hidup antara semua
pemeluk-pemeluk agama yang berlain-lainan di Tanah Air.
Kebebasan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa terjamin sepenuhnya berdasarkan pasal 29 Undang-
Undang 45. Ini juga berarti jaminan akan kebebasan menyiarkan
agama, kebebasan beralih agama dan keyakinan serta
berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keleluasaan
mendirikan rumah-rumah ibadah. Yang penting adalah agar
semuanya itu dilaksankan sesuai dengan tatakrama, nilai-nilai,
kaidah-kaidah yang berlaku dalam peri kehidupan dan perilaku
bangsa Indonesia dan tetap dalam semangat dan memantapkan
persatuan dan kesatuan . . . .
Dari kutipan di atas, saya hanya ingin menekankan bagian yang menyangkut
kebebasan beragama. Di samping itu, kutipan-kutipan dari ucapan atau per-
nyataan Presiden Soeharto di sini saya pergunakan tidak untuk membenarkan
atau mendukung pemikiran saya. Saya tidak ingin melakukan fallacy of
authority. Presiden Soeharto, baik secara pribadi ataupun sebagai Kepala
Negara, bukan merupakan sumber kebenaran. Begitu pula halnya dengan
lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk MPR. Tetapi saya hendak
menunjukkan bahwa tidak semua pikiran dan kebijakan Pemerintah keliru atau
jelek. Yang benar tentu saja harus diakui sebagai benar. Saya harap pikiran dan
kebijakan yang sudah benar dan baik akan dianut dan dilaksanakan secara
konsisten dalam segala bidang. Pikiran, pandangan, atau dasar dan pokok
kebijakan yang benar tidak selalu dan belum semuanya diterapkan atau
dilaksanakan dengan benar atau konsisten.
Selanjutnya, kebebasan agama sama sekali tidak sama, bahkan justru
bertentangan, dengan kewajiban beragama. Kebebasan itu merupakan hak, dan
hak itu mengandung pilihan, dipergunakan boleh, atau tidak dipergunakan juga
boleh, terserah pada yang bersangkutan. Nilai moral mewajibkan orang
beragama sama dengan melarang orang beragama, karena "melarang" dan
"mewajibkan" merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. "Melarang" adalah
mewajibkan untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.
Andaikata ada hukum yang mewajibkan orang untuk beragama, hukum itu tidak
akan ada artinya. Ia tidak akan mempunyai nilai operasional. Ia tidak akan
memiliki potensi enforcement, karena kepercayaan dan keyakinan adalah
masalah batiniyah, yang tidak dapat dinilai oleh orang lain, dan tidak bisa dicek
kebenarannya. Kepercayaan dan keyakinan tidak dapat dianggap selalu sama
dengan apa yang diucapkan atau diaku orang secara eksplisit. Oleh karena itu,
mewajibkan orang beragama hanya akan menanamkan kemunaflkan.
Memang, dengan kebebasan agama, atau tanpa kewajiban beragama, orang dapat
beragama apa saja, berganti agama kapan saja dia mau apa pun alasannya, atau
tidak beragama samasekali. Yang penting adalah bahwa apa pun pilihannya,
pilihan itu dilakukan atas dasar dan dalam iklim kebebasan, bukan karena
tekanan atau paksaan, sedangkan masalah keyakinan atau kepercayaan adalah
masalah dia sendiri sepenuhnya, yang hanya dapat diketahui oleh dirinya sendiri,
dan tentu saja oleh Tuhan.
Orang boleh percaya apa saja atau tidak percaya apa pun, sepanjang hal itu tidak
mengganggu hak atau kepentingan orang lain dan tidak mengganggu ketertiban
umum atau merugikan kependngan umum. Jika hal itu terjadi, menjadi
kewajiban negara untuk melakukan campur-tangan, tetapi bukan karena
seseorang tidak beragama atau tidak percaya Tuhan, atau karena kepercayaan
srang dianggap "sesat" seperti sudah dikatakan sebelumnya.
Politik & Kekuasaan
Saya mempergunakan istilah kehidupan politik dalam pengertian kehidupan
demokrasi. Hanya dalam sistem demokrasi pada dasarnya setiap orang
mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan
politik. Pada hemat saya, umat beragama justru harus aktif ikut serta dalam
kehidupan politik, tidak menjauhinya dan sekedar menjadi penonton, dengan
dalih politik itu kotor.
Para pemikir memberikan berbagai definisi tentang politik. Tetapi nampak
terdapat kesepakatan, pengertian politik itu menyangkut suatu jenis
kekuasaan, yaitu kekuasaan politik.
Kekuasaan juga terdapat dalam hubungan keluarga, yaitu kekuasaan seorang
suami atas isterinya atau sebaliknya, kekuasaan seorang ayah atau isteri atas
seluruh keluarga dan atas para pembantu atau kalau jaman dulu "budak"t atau
kekuasaan seluruh keluarga atas pembantu. Tetapi dalam pemikiran yang mula-
mula dikembangkan oleh para pemikir kuno seperti Aristoteles dari Yunani,
"kekuasaan politik" itu hanya terdapat dalam apa yang disebutnya sebagai polis
atau "perserikatan politik". Dia membedakan kekuasaan politik dari "kekuasaan"
dalam keluarga.
Sebab itu, kekuasaan dalam keluarga bukan objek pemikiran politik. Ia bukan
objek ilmu politik, karena berada di luar bidang atau kehidupan politik. Sebab itu
pula, sambil lalu dalam hubungan ini dapat saya sebutkan bahwa atas dasar itu
maupun pertimbangan-pertimbangan lain, saya meragukan pengertian
Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang diliputi semangat kekeluargaan
atau dilandasi asas kekeluargaan, yang memang tidak pernah diberi penjelasan
secara memadai dan tidak memiliki nilai operasional yang jelas.
Pengertian "perserikatan politik" atau polis itu kemudian dikembangkan oleh
Max Weber (1864-1920) sebagai perserikatan (association) dimana perintah-
perintahnya dilaksanakan dalam suatu wilayah tertentu dengan penggunaan atau
ancaman kekuatan fisik. Tetapi dalam berbicara tentang politik yang menyang-
kut penggunaan kekuasaan itu, para pemikir politik tidak menyinggung masalah
motivasi di belakang kekuasaan itu.
Hal itu berarti bahwa pada dasarnya kekuasaan itu dapat dipergunakan untuk
tujuan apa pun. Ini tergantung pada jenis sistem politik yang berlaku. Dalam
suatu (absolute monarchy), pada dasarnya penggunaan kekuasaan sang raja
ditujukan secara langsung ataupun tak langsung untuk memenuhi segala kepen-
tingan pribadinya sendiri atau yang dalam pandangan dia seorang diri dianggap
baik. Kalau pun dia memperhatikan kepentingan rakyatnya, kepentingan itu pada
akhirnya dinilai dari segi kepentingan dia sendiri juga.
Apa yang diimpikan oleh Plato sekitar dua-ribu limaratus tahun yang lalu
sebagai philosopher king, atau yang saya kira dalam bahasa Jawa dikenal
sebagai ratu adil atau pandito ratu, hanya ada dalam dunia ide atau dunia ideal.
Dia tidak pemah ditemukan dalam dunia nyata. Ini diakuinya juga oleh Plato
sendiri, khususnya dalam bukunya Republik.'5
Hal yang sama dapat dikatakan tentang sistem diktator. Perbedaan seorang
diktator dari seorang raja yang absolut mungkin hanya dalam soal bagaimana
seorang diktator, militer atau sipil, memperoleh kekuasaannya dan memberi
legitimasi kekuasan itu, untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Seorang raja
naik tahta terutama karena latar-belakang keturunannya, dan legitimasi
kekuasaannya biasanya diterangkan dengan teori "wahyu ilahi" atau divine right
of the king, sejarah, tradisi, dsb. Seorang diktator biasanya memperoleh
kekuasaan melalui perebutan kekuasaan dengan atau tanpa kekerasan. Dan dia
memberi legitimasi kekuasaannya serta membenarkan tindakantindakan dalam
menggunakan kekuasaan itu dengan berbagai dalih seperti
"kepentingan/keamanan nasional". Apakah dalihdalih itu benar, ataukah sekedar
kedok untuk menutupi kepentingan pribadinya sendiri adalah soal lain.
Sebaliknya, pemikiran demokrasi, yang melahirkan demokrasi sebagai sistem
politik, memberi motivasi di belakang penggunaan kekuasaan politik, yaitu
kepentingan rakyat banyak, karena dalam sistem demokrasi kekuasaan itu
berasal dari rakyat. Sebab itu, kata-kata Abraham Lincoln dalam pidatonya di
Gettysburg tahun 1863 pada kesempatan dedikasi makam pahlawan, tentang
"pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", sering dikutip sebagai
definisi demokrasi, kalaupun tanpa diketahui dari mana asal kata-kata itu.
Kepentingan rakyat itu dapat dinyatakan dalam berbagai rumusan dan dengan
titik-berat yang kelihatan berbeda, entah kesejahteraan umum, kebebasan,
keadilan, persamaan, demokrasi, atau yang lain. Ini seringkali dinyatakan atau
dirumuskan dalam ideologi. Tetapi pemahaman yang benar dan lengkap tentang
demokrasi sebagai ide, akan meliputi cita-cita itu semua. Rumusan kita
mengambil bentuk Pancasila.
Untuk menjaga, agar sistem demokrasi memang benar dipergunakan untuk
melayani kepentingan rakyat, atau dengan kata lain untuk mewujudkan cita-cita
demokrasi, berbagai mekanisme dikembangkan yang didasarkan pada konstitusi,
hukum dan perundang-undangan sebagai aturan permainan, baik dalam bentuk
tertulis maupun ddak tertulis (konvensi). Meskipun demikian, betapa pun
majunya, sebagai suatu sistem politik, demokrasi tidak akan pemah mencapai
kesempumaan. Setiap sistem politik selalu memberi peluang untuk manipulasi,
atau istilah yang di negeri ini semakin digemari orang sekurang-kurangnya
karena lebih halus, rekayasa. Rekayasa, apa lagi manipulasi, pada hakikatnya
adalah penyalahgunaan kekuasaan, hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh
demokrasi, atau pemanfaatan mekanisme demokrasi, terutama atau semata-mata
demi kepentingan pribadi atau kelompok (sektarian), yang bertentangan dengan
kepentingan umum.
Di saat seperti itulah, manakala terjadi penyalahgunaan kehidupan politik, kita
dapat mengatakan bahwa apa yang kita mengerti sebagai politik, yang
sebenamya ditujukan pada cita-cita yang baik dan luhur, dan sekurang-
kurangnya sebagai suatu alat bersifat netral, menjadi kotor. Tetapi di situlah
pula umat beragama justru dapat dan wajib menjalankan peranannya yang positif
dan konstruktif dalam kehidupan politik untuk membantu "membersihkan"
politik. Ajaran agama mewajibkannya demikian.
Ajaran Agama
Tetapi hal itu tidak berarti bahwa umat beragama wajib ikut serta dalam
kehidupan politik hanya ketika politik itu dilihatnya menjadi kotor, atau karena
politik itu memang kotor, atau semata mata untuk mencegah jangan sampai
politik menjadi kotor. Juga hal itu tidak berarti bahwa pemeluk agama apa pun,
sebagai manusia biasa seperti yang lain-lain, tidak dapat justru ikut membuat
politik itu kotor.
Dari segi Kristiani, partisipasi dalam kehidupan politik merupakan penjabaran
dari penghayatan ajaran agama dan kehidupan keagamaannya. Apakah inti
ajaran Kristiani itu? Ketika seorang Farisi bertanya dengan maksud untuk
mencobai Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum taurat?,
jawab Yesus kepadanya:
Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum
yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang
sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh
hukum Taurat dan kitab para nabi (Mat. 22: 34-40).
Itulah hakikat ajaran agama Kristen, ringkasan dalam dua kalimat, seluruh ajaran
Yesus kepada para pengikutnya. Cinta-kasih dan pengabdian manusia kepada
Tuhan harus dijabarkan dalam dan melalui cinta-kasih dan pengabdian kepada
sesamanya. Bagaimana orang dapat mengaku mencintai dan mengabdi Tuhan,
yang tidak dapat ditangkap oleh panca-indera manusia, jika dia tidak dapat
mencintai dan mengabdi sesamanya, yang nyata dan dapat dijangkau dengan
panca-indera?
Ajaran itu disampaikan melalui berbagai cara. Doa Bapa Kami, yang diajarkan
oleh Yesus sendiri kepada para pengikutnya, juga memuat pesan itu: Dan
ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada
kamt. Dan kata Yesus setelah mengajarkan doa itu, Karena jikalau kamu
mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu
juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan
mengampuni kesalahanmu. (Mat 6 14-15).
Pesan yang serupa mengenai cinta kasih pada sesama atau di antara sesama
manusia juga disampaikan melalui kata-kata Yesus, ... jika engkau
mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan
sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah
persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan
saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." (MaL 5
2y24).
Siapa sesama kita? Yang kita mengerti biasanya adalah orang-orang di sekitar
kita, dalam lingkungan yang dapat kita jangkau, ya lingkungan keluarga,
lingkungan sanak-saudara, kerabat dan handai-taulan, lingkungan di mana kita
hidup, dan lingkungan di mana kita bekerja dan berkarya.
Tetapi Yesus mengharapkan lebih dari itu. Sesama manusia itu bukan semata-
mata sesama saudara atau kerabat dan handai-taulan dalam pengertian tertentu,
mungkin sesama saudara yang sealiran, seiman, seagama, satu suku, satu bidang
kerja, atau dalam kelompok-kelompok yang dihimpun oleh faktor-faktor
pengikat dan pemersatu lainnya. Mereka harus menerapkan cinta-kasih itu juga
di luar lingkungan seperti itu, artinya, pada siapa saja, bahkan yang tidak pemah
kita kenal, atau bahkan mereka yang memusuhi kita. Kata-kata Yesus:
... Aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi
mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah
kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang
menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang
tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi
kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat
demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada
saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan
orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun
berbuat demikian? (Mat. 5: 44-47).
Ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku
manusia?, Yesus menjawab dengan mengisahkan sebuah cerita tentang orang
Samaria:
... Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho; ia jatuh
ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya
habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu
pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang
imam turun melalui jalan itu; ia melihat orang itu, tetapi ia
melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi
datang ke tempat itu; ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya
dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria, yang sedang
dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika ia melihat orang itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu
membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan
minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas
keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat
penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan
dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: Rawatlah dia
dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya,
waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut
pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke
tangan penyamun itu? Jawab orang itu: Orang yang telah
menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya:
Pergilah, dan perbuatlah demikian! (Luk. 10: 29 - 37).
Sesama manusia itu berlaku dari lingkungan yang sesempit-sempitnya sampai
lingkungan yang berskala nasional dan global. Orang Kristen bukan sekedar
anggota Gerejanya, tetapi juga anggota masyarakat yang lebih luas, sebagai
warga negara, dan sebagai manusia, ia juga warga dunia. Di sinilah aspirasi
keagamaan, dalam hal ini aspirasi Kristen, dapat difahami dan dihayati dalam
kerangka wawasan kebangsaan dan kemanusiaan, dan dengan demikian dalam
kerangka Pancasila.
Pada akhir hayatnya, praksis cinta-kasih dan pengabdian pada sesama itulah pula
yang akan menjadi ukuran pengadilan Tuhan atas prestasi hidup manusia selama
di dunia, seperti dilukiskan dalam perumpamaan berikut:
Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaanNya dan semua
malaikat bersama-sama dengan Dia, maka la akan bersemayam di
atas takhta kemuliaanNya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan
di hadapanNya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari
pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari
kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah
kananNya dan kambing-kambing di sebelah kiriNya. Dan Raja itu
akan berkata kepada mereka yang di sebelah kananNya: Mari, hai
kamu yang diberkati oleh BapaKu, terimalah Kerajaan yang telah
disediakan sejak dunia dijadikan. Sebab ketika Aku lapar, kamu
memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku
minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku
tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian;
ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku dalam penjara,
kamu mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar itu akan
menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat
Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan
kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat
Engkau orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau
telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami
melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi
Engkau?
Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah
seorang dari SaudaraKu yang paling hina ini, kamu telah melaku-
kannya untuk Aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang
di sebelah kiriNya: Enyahlah dari hadapanKu, hai kamu orang-
orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah
sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya.
Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika
Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum, ketika Aku seorang
asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku
telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit
dan dalam penjara, kamu tidak melawat Aku. Lalu mereka pun
akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami Engkau
lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau
sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka
Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang
paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. Dan
mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang
benar ke dalam hidup yang kekal. (Mat. 25: 31-46).
Nilai Kekuasaan Politik
Tentu saja wajar, mengingat inti pengertian "politik" seperti diuraikan secara
singkat di atas, bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik agar
dapat memperoleh kekuasaan. Kehidupan politik memang menyangkut kekuasa-
an, bagaimana memperoleh, membagi, dan menggunakan kekuasaan (kekuasaan
politik). Jenis maupun besar kekuasaan biasanya dikaitkan dengan kedudukan
atau jabatan tertentu. Kekuasaan dalam kehidupan politik dapat bersifat
legislatif, eksekutif, ataupun yudikadf, sesuai dengan pola pembagian kekuasaan
dalam sistem politik yang ada, sedangkan besar kekuasaan tergantung pada
jenjang jabatan atau kedudukan dalam hirarki sistem politik itu.
Sebab itu wajar pula, dan manusiawi, bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam
kehidupan politik dengan tujuan yang lebih konkrit lagi, yaitu agar dapat
menduduki sesuatu jabatan dalam salah satu cabang dan tingkat pemerintahan
dengan segala macam perks, trapptngs dan fasilitasnya. Tetapi jika harapan,
ekspektasi atau keinginan seperti itu sebagai motif dalam kehidupan politik
sifatnya egoistis, semata-mata demi kepentingan diri-sendiri, apa pun bentuk dan
manifestasinya, maka motivasi itu tidak mencerminkan sikap, pandangan, dan
semangat yang diilhami iman Kristiani.
Dengan motif seperti itu, orang memasuki kehidupan politik dengan pertanyaan-
pertanyaan, kalaupun tidak selalu dikemukakan secara eksplisit, yang intinya
lebih-kurang sebagai berikut: "Jabatan atau kedudukan apa yang dapat saya raih,
dan dengan hak dan wewenang apa saja? Imbalan dan fasilitas apa saja yang
dapat saya nikmati? Dengan kedudukan seperti itu, bagaimana prospek
kemajuan dan masa depan karier politik saya?"
Jika orang ikut serta dalam kehidupan politik dengan semangat keagamaan
seperti diuraikan sebelumnya, pertanyaanpertanyaan di atas seharusnya dibalik.
Pertanyaannya bukanlah semata-mata "Apakah yang dapat saya peroleh dari
partisipasi dalam kehidupan politik?", melainkan "Apakah yang dapat saya
perbuat dalam kehidupan politik, sehingga dengan demikian saya dapat
menyumbang pada kependngan dan kesejahteraan umum?"
Ucapan Presiden John Kennedy dalam pidato pelantikannya bulan Januari 1961
yang hingga sekarang terkenal, mengandung makna yang sama: ... ask not
what your country can do for you - ask what you can do for your country.
Kebetulan, Kennedy adalah satu-satunya Presiden Katolik yang pernah berkuasa
sepanjang sejarah Amerika Serikat hingga kini, yaitu selama lebih dari dua ratus
tahun lamanya. Saya tidak tahu, apakah Presiden Kennedy menyadarinya, karena
sebenarnya dia sekedar merubah kata-kata orang lain, meskipun ucapan itu,
khususnya dalam rumusan seperti itu, kini dikaitkan dengan Presiden Kennedy
pribadi. Tetapi bagaimanapun, itulah cermin sikap dan semangat Kristiani, yang
dilandasi oleh iman Kristiani.
Kita harus meletakkan kepentingan pribadi dan kelompok pada proporsinya.
Kepentingan seperti itu tidak merugikan kepentingan orang lain, dan tidak harus
dikorbankan, jika sejajar dan terpadukan dengan kepentingan yang lebih besar,
menjadi bagian integral dari kepentingan kesejahteraan umum. Dan dengan
melayani atau mengabdi kepentingan umum, kita sebenarnya sekaligus juga
melayani kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok kita masing-
masing. Kalau tidak, juga istilah kepentingan umum akan kehilangan artinya.
Berkaitan dengan hubungan antara kepentingan pribadi atau kelompok dan
kepentingan umum, dapat dikatakan bahwa nilai suatu jabatan atau kedudukan
politik, dengan demikian nilai kekuasaan politk, terletak dalam potensi atau
peluang yang disediakannya untuk memberi sumbangan pada kepentingan
kesejahteraan umum. Potensi atau peluang itu umumnya lebih besar, luas dan
efektif daripada potensi dan peluang perorangan atau kelompok. Tetapi
manakala jabatan atau kedudukan politik yang membawa kekuasaan politik itu
lebih, apalagi hanya diabdikan pada kepentingan pribadi atau kelompok, maka
terjadilah penyelewengan, manipulasi atau penyalahgunaan. Bahwa kekuasaan
politik di samping itu biasanya juga membawa keuntungan pribadi atau
kelompok, masih berada dalam batas-batas kewajaran, sepanjang hal itu tidak
mengorbankan kepentingan umum, sesuai dengan pemikiran yang diuraikan di
atas.
Kegiatan Keagamaan & Politik
Perintah Tuhan untuk mencintai sesama, yang dijabarkan dalam berbagai bentuk
kegiatan untuk kepentingan umum, sebenarnya telah dilaksanakan oleh berbagai
kelompok keagamaan maupun kelompok-kelompok sosial dan kemanusiaan
lainnya dari sektor swasta sepanjang jaman. Kita dapat mencatat apa yang
dikenal sebagai gerakan karitatif, yaitu usaha-usaha sosial dan kemanusiaan
untuk membantu kaum miskin dan anakanak yatim-piatu, aksi-aksi serupa yang
sering dikaitkan dengan hari raya keagamaan.
Meskipun demikian,usaha-usaha seperti itu umumnya sangat terbatas ruang-
lingkup dan efektifitasnya, karena sering kali bersifat insidental, kekurangan
dana maupun sumber daya manusia yang andal dan bersinambung. Lagi pula,
kegiatan seperti itu tidak jarang terbatas jangkauannya pada kalangan keagamaan
tertentu dengan berbagai macam implikasinya.
Lebih penting lagi, kegiatan karitatif, yang dari namanya jelas mencerminkan
cinta-kasih, hendaknya tidak diartikan semata-mata sebagai belas-kasihan.
Kegiatan karitatif seringkali cenderung ke arah pengertian itu, meskipun belas-
kasihan pada orang yang membutuhkan tetap merupakan suatu kebajikan, dan
satu aspek dari cinta-kasih.
Tetapi setiap orang memiliki harga diri dan pada dasarnya tidak suka dikasihani,
karena rasa kasihan dapat melukai harga diri itu. Oleh sebab itu, setiap orang
perlu semakin diperlakukan lebih sebagai subjek yang mandiri daripada semata-
mata sebagai objek yang dependen. Sekurang-kurangnya hal itu harus mcnjadi
salah satu tujuan pokok kegiatan karitatif, dan harus ada proses ke arah itu.
Cinta-kasih perlu difahami dan dihayati lebih secara rasional daripada secara
emosional semata.
Dalam hubungan ini, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik yang
dikutip di atas mungkin juga perlu difahami lebih luas dan lebih jauh daripada
sekedar suatu contoh belas-kasihan, yang biasanya dikaitkan dengan perasaan.
Dan sebenarnya apa yang diperbuat oleh orang Samaria dalam cerita itu
merupakan suatu perbuatan yang rasional dan tidak banyak mencerminkan
perasaan.
Dalam hubungan itulah kita dapat memahami arti kehidupan politik. Setiap
orang pada dasarnya perlu dan wajib berpartisipasi dalam kehidupan politik,
karena politik menyentuh kehidupan semua orang secara langsung. Lebih
penting lagi, politik merupakan wahana paling efektif bagi usaha menciptakan
kesejahteraan umum. Untuk inilah negara dan pemerintahannya dibentuk,
terutama yang berasaskan demokrasi.
Pertama, kebijakan pemerintah (negara) didukung oleh kekuasaan yang efektif.
Kedua, kebijakan pemerintah lebih efektif dalam arti menjangkau wilayah yang
lebih luas dan jumlah penduduk yang lebih besar. Ketiga, kebijakan pemerintah
lebih efektif dalam arti tidak terbatas pada kelompok agama tertentu, melainkan
ditujukan kepada rakyat tanpa membedakan latar-belakang agama, suku, ras,
dsb. Kegiatan karitatif kelompok-kelompok keagamaan tidak jarang menjadi
sasaran prasangka dan kecurigaan, karena dihubungkan dengan usaha
proselitisasi atau dakwah. Dan keempat, kebijakan pemerintah memiliki sumber
dana yang bersinambung dan sumber daya manusia yang lebih profesional,
kalaupun belum tentu lebih andal, karena kelompok keagamaan didorong oleh
motif idealisme yang mungkin lebih kuat.
Potensi, peluang, dan efektivitas lebih besar yang dimungkinkan oleh kehidupan
politik bagi usaha menciptakan kesejahteraan umum tidak berarti bahwa
kegiatan karitatif kelompok keagamaan ataupun kelompok-kelompok sosial dan
kemanusiaan lainnya dari sektor swasta tidak bernilai dan bermanfaat lagi.
Sebaliknya, jenis kegiatan itu dapat merupakan pelengkap kebijakan
pemerintahan demi tujuan yang sama.
Di samping perbedaan antara dua jenis kegiatan itu yang menyangkut ruang-
lingkup dan efektivitas, mungkin terdapat satu perbedaan lagi yang penting.
Kegiatan pemerintahan tidak disertai usaha-usaha keagamaan, sedangkan
kegiatan karitatif kelompok keagamaan memang sering disertai usaha-usaha
proselitisasi atau pengembangan agama tertentu.
Sebenarnya, pada prinsipnya kegiatan seperti itu seharusnya wajar-wajar saja,
sepanjang hal itu didasarkan pada asas kebebasan dan keterbukaan, tanpa
tekanan dalam bentuk apa pun. Kegiatan sosial dan kemanusiaan hendaknya
tulus, tidak sekedar menjadi dalih atau kedok bagi tujuan-tujuan lain yang belum
tentu mulia sebagaimana dinyatakan. Bagaimana pun, masalah seperti ini telah
menjadi peka antara umat berbagai agama, karena adanya kesan penekanan,
"umpan", dan persaingan yang tidak sehat dan adil, sehingga perlu ditangani se-
cara hati-hati, penuh pengertian dan iktikad baik pada semua pihak yang
bersangkutan.
Agama vs. Politik
Saya yakin bahwa komitmen untuk mengabdi kepada sesama pada dasarnya
diajarkan dan didambakan oleh semua agama. Ajaran setiap agama dimaksudkan
sebagai ajaran yang bersifat universal untuk segenap umat manusia dari segala
jaman. Tetapi tentu saja menjadi hak setiap orang untuk memilih ajaran agama
mana yang diyakini, dan oleh karena itu difahami, dianut dan dihayatinya. Orang
juga bebas untuk berubah pikiran dan pendirian dalam hal itu, apa pun
alasannya, asal dengan kebebasan seperti dikemukakan sebelumnya.
Tidak seorang atau sekelompok manusia pun di dunia ini dapat mengklaim
memiliki, apalagi dengan monopoli, seluruh kebenaran, dan memaksakannya
pada orang atau kelompok lain. Kaum komunis berbuat demikian. Semua agama
"menyumbang" kebenaran, dan masing-masing memiliki sebagian dari
kebenaran.
Meskipun demikian, menjadi hak setiap orang untuk meyakini apa yang
diajarkan oleh agamanya sebagai kebenaran. Dan menjadi kewajiban semua
orang untuk saling menghargai dan mcnghormati keyakinan itu. Ini merupakan
landasan toleransi dan kerukunan. Suatu ucapan bijak dari Cina menyebutkan
adanya tiga kebenaran, yaitu kebenaranmu, kebenaranhu, dan kebenaran itu
sendiri (the truth).
Apakah implikasinya bagi keterlibatan atau partisipasi umat beragama dalam
kehidupan politik atau kehidupan kenegaraan di negara Pancasila ini? Yang
paling penting adalah bahwa negara harus berdiri di luar semua golongan agama,
dan sebab itu tidak mendasarkan sistem hukum dan perundang-undangannya
pada ajaran agama tertentu. Dengan demikian tidak terjadi perpaduan antara
kewajiban seseorang sebagai warga negara (civil obligations), yang diatur oleh
negara, dan kewajiban keagamaan (religious obligations), yaitu kewajiban
sebagai umat beragama, yang diatur oleh agama, tetapi tidak memiliki kekuatan
hukum negara, dan oleh karena itu tidak memiliki civil effect.
Dengan kata lain, ajaran dan hukum agama tidak mengikat negara, atau menjadi
landasan dan bagian dari sistem hukum dan perundang-undangan negara. Dan
sebaliknya, ajaran dan hukum agama tidak diberi sanksi atau diperkuat oleh
hukum negara. Kewajiban negara dalam bidang keagamaan adalah menciptakan
iklim yang sehat untuk menunjang kehidupan beragama yang bebas dan
mendorong kerukunan umat berbagai agama. Tetapi negara tidak akan
mengenakan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum atau ajaran
agama, sepanjang hal itu tidak sekaligus merupakan hukum negara yang
merupakan pelaksanaan tugas negara dalam memelihara ketertiban umum,
misalnya mencuri atau membunuh. Dari sebab itu, negara Pancasila bukan
negara agama atau teokrasi. Tetapi saya keberatan dengan pengertian negara
Pancasila (begitu juga demokrasi Pancasila) dengan rumusan yang serba negatif,
yang serba bukan-bukan seperti itu, karena biasanya juga dikatakan negara
Pancasila bukan negara sekuler.
Istilah sekuler di negeri ini mempunyai konotasi yang serba negatif, menurut
pendapat saya karena distorsi atau misinterpretasi istilah atau konsep itu, sadar
atau tidak, seperti halnya dengan istilah "liberal". Sekularisasi cenderung
dikacaukan dengan sekularisme. Pada tanggal 26 Mei 1980, ketika me-
nyampaikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Nasional ke II Majelis
Ulama Indonesia di Istana Negara, antara lain Presiden Soeharto mengatakan,
bahwa:
Negara kita jelas bukan negara agama. Artinya negara kita tidak
didasarkan atas sesuatu agama. Hal ini sesuai dengan keadaan
masyarakat kita yang serba majemuk: yang terdin dari berbagai
suku, yang memiliki aneka ragam adat dan kebiasaan, yang
memeluk agama yang berbeda-beda. Sikap rukun dan bersatu di
antara golongan masyarakat yang berbeda-beda itu adalah salah
satu ciri dan kepribadian kita yang kuat dan perlu kita pelihara
bersama.
Namun negara kita juga bukan negara yang mengabaikan agama.
Negara kita bukan negara sekular. Negara sekular tidak sesuai
dengan pola budaya bangsa kita yang sangat kuat rasa
kebersamaan dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.
Saya memahami Negara Pancasila pada dasarnya sebagai negara sekuler. Saya
tidak mempergunakan istilah sekularisme, yang kalaupun tidak anti-agama,
sekurang-kurangnya tidak memberi perhatian pada agama, sedangkan Negara
Pancasila justru memberi perlindungan dan pengayoman, serta menyediakan
iklim yang memungkinkan kehidupan beragama secara bebas, dan kerukunan
serta toleransi saling menghormati antar umat berbagai agama. Saya memahami
negara Pancasila pada dasarnya sebagai negara sekuler, dalam pengertian yang
sederhana, yang terbatas pada yang esensial saja, yaitu bahwa di negara ini
terdapat pemisahan, atau tidak terjadi perpaduan antara kekuasaan agama dan
kekuasaan politik. Bahwa negara atau pemerintah memberikan perlindungan
atau "pengayoman" bagi kehidupan beragama dan menjamin atau membantu
menciptakan iklim yang memungkinkan dan mendorong kebebasan beragama
dan kerukunan hidup beragama, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi,
yang menjamin hak azasi manusia, termasuk kebebasan beragama.
Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama dapat menjadi faktor
pemersatu dalam arti membantu memperkokoh dan memelihara persatuan
kebangsaan Indonesia, dan dengan demikian membantu memperkuat
penghayatan wawasan kebangsaan Indonesia, jika : Pertama, umat berbagai
agama dapat mengembangkan pemahaman bersama tentang konsep dan
wawasan kebangsaan Indonesia, dan mempunyai komitmen bersama pada
persatuan bangsa.
Kedua, umat berbagai agama dapa mengmbangkan pemahaman dan wawasan
bersama tentang kedudukan dan peranan agama dalam negara Pancasila. Ini
meliputi terutama pengertian kita tentang Pancasila sebagai sjumber hukum, dan
tentang kebebasan beragama.
Dan ketiga, jika umat berbagai agama bersama-sama memerangi segala bentuk
ketidakdilan. Dengan begitu kita bersama-sama berjuang menegakkan keadilan
dan kesejahteraan umum dalam masyarakat sebagai penghayatan kehidupan
keagamaan masing-masing.
Dengan persamaan-persamaan seperti itu, kita dapat berharap semakin terbina
dan terpeliharanya kerukunan dan kerjasama antar umat beragama di Indonesia.
Ini semua akan membantu menjamin stabilitas dan perdamaian nasional,
yang
memungkinkan kita semua bergerak maju ke arah cita-cita bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka dan berdaulat.***
Anda mungkin juga menyukai
- A.nasionalisme Bangsa IndonesiaDokumen19 halamanA.nasionalisme Bangsa IndonesiaIbnu AnugrahBelum ada peringkat
- Integrasi Nasional Dan Pluralitas Masyarakat IndonesiaDokumen6 halamanIntegrasi Nasional Dan Pluralitas Masyarakat IndonesiaEsternia Gladys SBelum ada peringkat
- Ancaman Terhadap Integrasi NasionalDokumen7 halamanAncaman Terhadap Integrasi NasionalRifdah Eli AriantiBelum ada peringkat
- Ketahanan NasionalDokumen3 halamanKetahanan Nasionaltotoro ChanBelum ada peringkat
- Nasionalisme Kaum MudaDokumen18 halamanNasionalisme Kaum Mudaadinda agustinBelum ada peringkat
- Perbedaan Pancasila Liberalisme KomunismeDokumen2 halamanPerbedaan Pancasila Liberalisme KomunismeIto CoolBelum ada peringkat
- Kelompok 5 WBK Wbbmdocx PDF FreeDokumen23 halamanKelompok 5 WBK Wbbmdocx PDF FreeDella BkyBelum ada peringkat
- Contoh Soal PASDokumen1 halamanContoh Soal PASAgus SetiawanBelum ada peringkat
- Makalah NasionalismeDokumen16 halamanMakalah NasionalismeTafta Na E'iBelum ada peringkat
- Makalah Pemberantasan KorupsiDokumen37 halamanMakalah Pemberantasan KorupsiH4 22 ULFA TENRI AJENGBelum ada peringkat
- Kelompok 16 - EksistensialismeDokumen8 halamanKelompok 16 - EksistensialismePengisi DompetBelum ada peringkat
- Macam Macam PenalaranDokumen9 halamanMacam Macam PenalaranMuhammad YunusBelum ada peringkat
- KELOMPOK 4 - KTI Pengaruh DietDokumen21 halamanKELOMPOK 4 - KTI Pengaruh DietHafidz AlfarisiBelum ada peringkat
- 1920 BAB 6 Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan Terhadap NKRIDokumen26 halaman1920 BAB 6 Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan Terhadap NKRIDevin Jonathan ThedyBelum ada peringkat
- Ketahanan Nasional Dan Bela Negara Dalam Membangun Komitmen Kolektif KebangsaanDokumen17 halamanKetahanan Nasional Dan Bela Negara Dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaanatin irmayaBelum ada peringkat
- 2 A.tantangan Pancasila SBG Dasar Negara Untuk Menanggulangi KorupsiDokumen18 halaman2 A.tantangan Pancasila SBG Dasar Negara Untuk Menanggulangi KorupsiHaris GarnisunBelum ada peringkat
- Materi 3. Dinamika Perumusan Dan Perjalanan Hidup PancasilaDokumen30 halamanMateri 3. Dinamika Perumusan Dan Perjalanan Hidup PancasilaHezron'Dwi Setiantwo BagaBelum ada peringkat
- URGENSI INTEGRASI NASIONAL Pertemuan 3Dokumen22 halamanURGENSI INTEGRASI NASIONAL Pertemuan 3Hanafy Naufal100% (1)
- Makalah Pradigma Pengembangan IPTEKSDokumen18 halamanMakalah Pradigma Pengembangan IPTEKSMiftahul HidayahBelum ada peringkat
- Makalah Puasa RamadhanDokumen11 halamanMakalah Puasa RamadhanTito IbnuBelum ada peringkat
- Makalah Konsep GeopolitikDokumen7 halamanMakalah Konsep GeopolitikSyaifulNazrulBelum ada peringkat
- Dampak Penegakan Hukum PDFDokumen2 halamanDampak Penegakan Hukum PDFVhivhie PoenhyaBelum ada peringkat
- Kelompok 7 Persiapan Penyajian LisanDokumen21 halamanKelompok 7 Persiapan Penyajian LisanNurshafira SuardiBelum ada peringkat
- KLP.8dinamika Historis Dan Urgensi Wawasan NusantaraDokumen15 halamanKLP.8dinamika Historis Dan Urgensi Wawasan NusantaraYusranBelum ada peringkat
- Makalah Klasifikasi Agama - Ibnu IlmiawanDokumen16 halamanMakalah Klasifikasi Agama - Ibnu IlmiawanIbnu Ilmiawan JuliantoBelum ada peringkat
- Katolik RomaaDokumen13 halamanKatolik RomaaBenetusBemaJordyBelum ada peringkat
- Refleksi Nilai Sumpah Pemuda Di Era KontemporerDokumen3 halamanRefleksi Nilai Sumpah Pemuda Di Era KontemporerHasnan RifkiBelum ada peringkat
- Hubungan PancasilaDokumen4 halamanHubungan PancasilaAndreas NatanaelBelum ada peringkat
- Makalah Jati Diri BangsaDokumen7 halamanMakalah Jati Diri Bangsaopieberliana100% (1)
- Makalah Kelompok 1 Pemeriksaan Genitalia Dan AnusDokumen17 halamanMakalah Kelompok 1 Pemeriksaan Genitalia Dan Anusfirman ziura ziuraBelum ada peringkat
- MAKALAH Identitas NasionalDokumen18 halamanMAKALAH Identitas NasionalLovelly HannyBelum ada peringkat
- Upacara Kematian Masyarakat Melayu Kalimantan BaratDokumen10 halamanUpacara Kematian Masyarakat Melayu Kalimantan BarataangantenkBelum ada peringkat
- Makalah KONSEP DASAR KOMUNIKASIDokumen18 halamanMakalah KONSEP DASAR KOMUNIKASIilham sukriBelum ada peringkat
- Isbd CintaDokumen8 halamanIsbd CintaArif RifandiBelum ada peringkat
- Sistem Perekonomian IndonesiaDokumen6 halamanSistem Perekonomian IndonesiaLaila ArridhoBelum ada peringkat
- Laporan Bahasa InggrisDokumen12 halamanLaporan Bahasa Inggrisbriandi pBelum ada peringkat
- Makalah Masalah GeostrategiDokumen8 halamanMakalah Masalah GeostrategiGani Adi Wiranata (Gani)Belum ada peringkat
- Kalimat Umum EditDokumen20 halamanKalimat Umum EditNovi AdripitaBelum ada peringkat
- Makalah Agama Kelompok 13Dokumen14 halamanMakalah Agama Kelompok 13Afira OltafianyBelum ada peringkat
- Makalah PKN (Pertahanan Nasional)Dokumen25 halamanMakalah PKN (Pertahanan Nasional)Ronald FransyaiguBelum ada peringkat
- Makalah Bahasa Indonesia "Ringkasan, Ikhtisar & Abstrak": Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas 2018Dokumen20 halamanMakalah Bahasa Indonesia "Ringkasan, Ikhtisar & Abstrak": Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas 2018Puan MaharaniBelum ada peringkat
- Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa PersatuanDokumen4 halamanBahasa Indonesia Sebagai Bahasa PersatuanNindya Anggi WulandariBelum ada peringkat
- Tugas Makalah AkulturasiDokumen15 halamanTugas Makalah Akulturasidesiariningsih22Belum ada peringkat
- TUGAS MAKALAH MATA KULIAH PancasilaDokumen10 halamanTUGAS MAKALAH MATA KULIAH PancasilaRetno AyunBelum ada peringkat
- Aliran FisiokratismeDokumen9 halamanAliran FisiokratismeAkif IrBelum ada peringkat
- Kumpulan Kata Ilmiah Dalam PolitikDokumen28 halamanKumpulan Kata Ilmiah Dalam PolitikUltramanCosmosBestHeroBelum ada peringkat
- Komunikasi Antar Budaya 1Dokumen5 halamanKomunikasi Antar Budaya 1indahBelum ada peringkat
- Pengertian Aliran Masa PencerahanDokumen14 halamanPengertian Aliran Masa PencerahanSusi EnjoyBelum ada peringkat
- Kalimat Dan Kalimat Efektif Dalam Penulisan - 2013Dokumen48 halamanKalimat Dan Kalimat Efektif Dalam Penulisan - 2013Cynthia CynBelum ada peringkat
- Makalah Filsafat IlmuDokumen16 halamanMakalah Filsafat IlmuNurfadilah dilBelum ada peringkat
- Soal Ujian Akhir Semester PPKNDokumen2 halamanSoal Ujian Akhir Semester PPKNDaBelum ada peringkat
- Kewaspadaan NasionalDokumen15 halamanKewaspadaan NasionalVathia Putri ValiansiBelum ada peringkat
- Menelusuri Model Dan Menganalisis Teks Laporan PenelitianDokumen51 halamanMenelusuri Model Dan Menganalisis Teks Laporan PenelitianYoland EdoBelum ada peringkat
- Makalah Islam Dan MasyarakatDokumen13 halamanMakalah Islam Dan MasyarakatIndah YABelum ada peringkat
- Kunci Jawaban Tryout Ke-4Dokumen33 halamanKunci Jawaban Tryout Ke-4Diana Yahuji YusanBelum ada peringkat
- 13 Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan IlmuDokumen27 halaman13 Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan IlmuAprina PolmauliBelum ada peringkat
- Hidup Baru Dalam Iman Dan PengudusanDokumen3 halamanHidup Baru Dalam Iman Dan PengudusanApriani SentiaBelum ada peringkat
- 09 Bagaimana Urgensi Dan Tantangan Ketahanan Nasional Dan Bela Negara Bagi Indonesia Dalam Membangun Komitmen Kolektif KebangsaanDokumen20 halaman09 Bagaimana Urgensi Dan Tantangan Ketahanan Nasional Dan Bela Negara Bagi Indonesia Dalam Membangun Komitmen Kolektif KebangsaanyuliskaBelum ada peringkat
- Agama Makalah KerukunanDokumen12 halamanAgama Makalah KerukunanTubagus Bima Off-Onlinez88% (8)
- Pentingnya Kerukunan Umat Beragama PDFDokumen11 halamanPentingnya Kerukunan Umat Beragama PDFAnonymous w84ZK0o9zOBelum ada peringkat