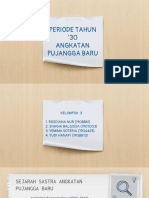Bukupuisi 18
Diunggah oleh
roekminto@yahoo.com0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
25 tayangan2 halamanJudul Asli
Bukupuisi18+
Hak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
25 tayangan2 halamanBukupuisi 18
Diunggah oleh
roekminto@yahoo.comHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 2
Refleksi Seorang Santri*
(Sebuah Resensi Buku)
Oleh : Fajar Setiawan Roekminto
Ditengah lesunya minat masyarakat terhadap kesusastraan, khususnya puisi,
serta sedikitnya orang yang “rela” menjadi penyair, terbitnya antologi puisi “18+”
(Delapan Belas Plus) karya Faaizi L. Kaelan memang sangat melegakan hati. Paling
tidak antologi ini bisa menjadi sebuah akses bagi perenungan dan pelarian dari hiruk
– pikuk kehidupan sehari – hari yang jumawa. Antologi ini sekaligus menjadi sebuah
ucapan syukur bahwa sebenarnya sastra tidak benar – benar “in memoriam.”
Dalam kata pengantarnya, penulis menyodorkan sebuah pertanyaan,
sekaligus juga mewakili pertanyaan mereka yang tidak tahu dan/atau tidak peduli
dengan puisi, “Apakah gunanya menghabiskan waktu berjam – jam untuk menulis
puisi…?” Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh penulisnya, “…karena suka – suka
saja. Saya memilih puisi sebagai media berekspresi…” (hal.5). Benar, puisi adalah
sebuah media untuk berekspresi, sama seperti misalnya lukisan yang merupakan
ekspresi pelukis, foto bagi fotografer dan lain sebagainya.
Pemilihan judul 18+, (Delapan belas Plus) merupakan ide penulisnya dalam
mengabadikan momentum historis perjalanan kepenyairannya. Delapan belas
adalah usia penulis antologi ini ketika mulai menulis puisi secara serius, yaitu ketika
ia duduk di kelas 2 Aliyah (setara SMU) (hal.6). Judul bukunya, “18+”, sekaligus
menjadi puisi pembuka dalam antologi ini, //Delapan belas tahun kemudian/ hidup
menemukan gairah// (hal.19). Sebagai sosok santri Madura yang sarat dengan
tradisi pesantren, pengetahuannya terhadap hal – hal yang berbau sekular
merupakan sesuatu yang luar biasa. Tema serta diksi yang ada dalam antologi ini
juga menjadi sebuah bukti bahwa sebagai santri, penulisnya adalah seorang yang
berpendidikan, terbuka, moderat dan bergaul dengan berbagai kalangan secara
luas. Puisi – puisinya tidak membelenggu eksistensinya sebagai manusia, namun
mengalir lugas dalam kata – kata yang terkesan nge-pop dan funky. Untuk itu
puisinya dengan mudah dipahami, baik oleh mereka yang mempunyai latar belakang
kesastraan maupun tidak sama sekali.
Sama seperti kebanyakan penyair, penulis antologi ini mencoba untuk
mengajak pembacanya merenung tentang kehidupan. Ajakan itu tidak disampaikan
secara agitatif dan meledak – ledak malah justru sebaliknya lembut, rendah hati dan
cenderung pesimis. Misalnya dalam Palestina: //Dan kini, tinggallah belasungkawa
yang basi/ mengalun perih tak tertakar/ maka lagukan himne tangis/ lewat
kesempitan cinta yang terjual// (hal.44). Rasa solidaritas, keprihatinan dan
kesedihannya sebagai seorang muslim dalam melihat penderitaan rakyat Palestina
tidak diekspresikan secara menggebu – gebu, marah dan penuh kebencian. Ada
semacam “himbauan” untuk mengembalikan segala persoalan kepada Tuhan
melalui bathin manusia yang tulus ikhlas, tanpa embel – embel kepentingan.
Kegundahan dan kemuakan penulis terhadap realitas yang artifisial
disampaikannya secara santun. Salah satunya adalah rasa muak terhadap orang
yang selalu mengobral janji namun tak pernah ditepati dan menjajakan kata namun
tanpa makna, //:dalam hal bicara,/ musik lebih fasih ketimbang kata – kata/ Da Vinci
menyulap Monalisa/ mata terbelalak, hati berdecak/ : satu lukisan, seribu kata
jumlahnya// Kataku kosong, kataku sunyi/ kata berkutat dalam wacana/ ke manakah
* Sebagian besar isi tulisan ini merupakan rangkuman pembicaraan
penulis dalam bedah buku “Antologi Seratus Puisi (18+)” di Institut
Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga” Yogyakarta. 15 Juni 2003.
perginya makna?// (hal.123). Konser amal musik bertajuk World Peace Music Award
yang di gelar di Garuda Wisnu Kencana Bali, pada tanggal 14/06, seolah – olah
mengamini syair ini. Dalam dunia yang serba nir orang baik, penulis
mengekspresikannya secara sederhana dan penuh kerendahan hati, //Untuk
menjadi orang baik – baik/ tak perlu kau gebukin// Untuk menjadi orang baik – baik/
tak perlu dana miliaran/ tapi cukup dengan sepotong keberanian/ untuk didengki/
dan siap untuk disakiti// (hal.130). Ajakan untuk melihat diri sendiri sebagai sosok
manusia yang utuh menjadi tema utama antologi ini, termasuk didalamnya
bagaimana kita berpikir dan berperilaku menuju kepada segala hal yang baik
dengan maksud agar umat manusia mampu menjadikan dunia yang sudah terlanjur
rusak dan kejam ini, (digambarkan dalam Antropologi Abad XXI), menjadi tempat
yang lebih nyaman untuk hidup. Antologi ini ditutup dengan ajakan untuk berdoa
bagi dunia dan bagi Indonesia tercinta ini, //Untuk menggapai kedamaian/ dunia
melahirkan alegori, tamsil dan teladan/ maka dibuatlah Indonesia/ bagi
kedermawanan sebuah negara donor darah/ : Aceh, Timor, Banyuwangi// Mari kita
berdoa;/ atas nama kedamaian/ jangan lagi dunia/memperebutkan air mata//
(hal.146).
Secara keseluruhan tema dan gaya dalam antologi puisi ini tidak sepenuhnya
baru dan berbeda dengan antologi puisi yang ditulis oleh penyair terdahulu, namun
menjadi berbeda ketika antologi ini hadir ditengah – tengah masyarakat yang
pragmatis dan cenderung anarkis. Antologi puisi ini mampu menjadi penyejuk.
*************
Anda mungkin juga menyukai
- Sejarah Perkembangan Puisi Di Indonesia (Aulia Hidayati)Dokumen22 halamanSejarah Perkembangan Puisi Di Indonesia (Aulia Hidayati)Diditz25% (4)
- Sejarah Sastra Angkatan Pujangga BaruDokumen22 halamanSejarah Sastra Angkatan Pujangga BaruSoteria Yemima100% (1)
- Seks Sastra Kita1Dokumen9 halamanSeks Sastra Kita1Abu WafaBelum ada peringkat
- Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaDari EverandSimbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (16)
- Bedah Buku Kumpulan Puisi Inilah Pamflet ItuDokumen19 halamanBedah Buku Kumpulan Puisi Inilah Pamflet ItuFathulloh MuzammielBelum ada peringkat
- Esai KompasDokumen14 halamanEsai KompasasyhariBelum ada peringkat
- Esai KompasDokumen14 halamanEsai KompasFikri Erlinda SetiyaniBelum ada peringkat
- Analisis Dan Penafsiran PuisiDokumen5 halamanAnalisis Dan Penafsiran PuisiEka Nurvita SariBelum ada peringkat
- Materi Pak KarjoDokumen11 halamanMateri Pak KarjoFadila Rana LalunaBelum ada peringkat
- BAB V Ideologi Dalam Gugur Merah PDFDokumen42 halamanBAB V Ideologi Dalam Gugur Merah PDFDr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum.Belum ada peringkat
- API Bawah Tanah: Pengakuan Malin Dan Premis Rantau Oleh Esha Tegar PutraDokumen6 halamanAPI Bawah Tanah: Pengakuan Malin Dan Premis Rantau Oleh Esha Tegar PutraEsha Tegar PutraBelum ada peringkat
- Analisis Kesusastraan Angkatan Pujangga BaruDokumen8 halamanAnalisis Kesusastraan Angkatan Pujangga BaruAndi Muhammad YusrilBelum ada peringkat
- Tugas Akhir Sosiologi Sastra AINAYADokumen16 halamanTugas Akhir Sosiologi Sastra AINAYAVhey AnmerBelum ada peringkat
- Angkatan Pujangga BaruDokumen11 halamanAngkatan Pujangga BaruniroelBelum ada peringkat
- Resensi 3 BukuDokumen3 halamanResensi 3 BukuFedi KurniawanBelum ada peringkat
- Analisis Puisi MH. Ainun NajibDokumen26 halamanAnalisis Puisi MH. Ainun NajibNancy Megawati SimanjuntakBelum ada peringkat
- BAB V Ideologi Dalam Gugur MerahDokumen36 halamanBAB V Ideologi Dalam Gugur MerahDr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum.Belum ada peringkat
- Kumpulan Puisi Penari Cinta Anak KoruptorDokumen166 halamanKumpulan Puisi Penari Cinta Anak KoruptorAkri SanjaniBelum ada peringkat
- CBR Bahasa Inggris Teori Dan Sejarah SastraDokumen21 halamanCBR Bahasa Inggris Teori Dan Sejarah SastraJenni Marlina SitanggangBelum ada peringkat
- 26 Serikat Puisi Zen HaeDokumen44 halaman26 Serikat Puisi Zen HaeMarisaGunawan100% (2)
- (Subagio Sastrowardoyo) Sosok Pribadi Dalam SajakDokumen210 halaman(Subagio Sastrowardoyo) Sosok Pribadi Dalam SajakAnggaTrioSanjayaBelum ada peringkat
- Latar Belakang Analisis Puisi "Kunyanyikan Lagu Ini" Karya Putu WijayaDokumen3 halamanLatar Belakang Analisis Puisi "Kunyanyikan Lagu Ini" Karya Putu Wijayaintan100% (1)
- CDokumen25 halamanCDwika ChyniiBelum ada peringkat
- Percakapan Dalam Kamar Dan Sehimpun Sajak Lain-2018Dokumen302 halamanPercakapan Dalam Kamar Dan Sehimpun Sajak Lain-2018kdaegaaBelum ada peringkat
- Puisi 20A - Ilham RabbaniDokumen2 halamanPuisi 20A - Ilham RabbaniIlham ErBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan PuisiDokumen5 halamanSejarah Perkembangan PuisiYoza TulahBelum ada peringkat
- Penyingkapan Reproduksi Otentisitas Dalam Manufaktur Kultural Kapitalisme LanjutDokumen14 halamanPenyingkapan Reproduksi Otentisitas Dalam Manufaktur Kultural Kapitalisme LanjutDwi PranotoBelum ada peringkat
- Puisi Fragmen Bulan HijauDokumen118 halamanPuisi Fragmen Bulan HijauPenulis RulisBelum ada peringkat
- BAB I PendahuluanDokumen15 halamanBAB I PendahuluanAkungabutcomBelum ada peringkat
- Kelompok 2 KesusasteraanDokumen17 halamanKelompok 2 KesusasteraanWahyu BUBelum ada peringkat
- 26 Serikat Puisi Zen HaeDokumen44 halaman26 Serikat Puisi Zen HaeIsin SurisinBelum ada peringkat
- Sejarah Munculnya Angkatan Pujangga BaruDokumen7 halamanSejarah Munculnya Angkatan Pujangga BaruAlexs SetiawanBelum ada peringkat
- Teori Kritik Sastra Indonesia Modern Pada Periode Kritik SastrawanDokumen16 halamanTeori Kritik Sastra Indonesia Modern Pada Periode Kritik SastrawanJoni Iskandar100% (1)
- Artikel Sastra IndonesiaDokumen4 halamanArtikel Sastra IndonesiaApe'IzaelBelum ada peringkat
- Sastra IndonesiaDokumen3 halamanSastra IndonesiaDikri RedDevilsBelum ada peringkat
- Gilang Fadlurrahman - Tugas 1Dokumen4 halamanGilang Fadlurrahman - Tugas 1Gilang FadlurrahmanBelum ada peringkat
- Contoh Kritik Sastra 1Dokumen4 halamanContoh Kritik Sastra 1Putra Workstation67% (3)
- Apresiasi Puisi "Terbuka Bunga" Karya Amir Hamzah Dan Novel "Olenka" Karya Budi DarmaDokumen30 halamanApresiasi Puisi "Terbuka Bunga" Karya Amir Hamzah Dan Novel "Olenka" Karya Budi Darmadhita murdaya0% (1)
- Angkatan Pujangga BaruDokumen87 halamanAngkatan Pujangga BaruLing Xiaoli100% (2)
- Analisis InterpretasiDokumen6 halamanAnalisis InterpretasiChua Dan C'j-one100% (1)
- Holmes QuarterCenturyIndonesian 1955Dokumen7 halamanHolmes QuarterCenturyIndonesian 1955edeledelieneBelum ada peringkat
- Menguak Lanskap Kesenian Dan Kebudayaan Sulsel Di Masa OrbaDokumen2 halamanMenguak Lanskap Kesenian Dan Kebudayaan Sulsel Di Masa Orbakebun kataBelum ada peringkat
- Puisi Dan Antipuisi PDFDokumen240 halamanPuisi Dan Antipuisi PDFabdulwmBelum ada peringkat
- Antologi Puisi Tadarus Dan Pahlawan Dan Tikus Karya A. Mustofa BisriDokumen263 halamanAntologi Puisi Tadarus Dan Pahlawan Dan Tikus Karya A. Mustofa BisriYin UdeBelum ada peringkat
- A (1) - Kapui Mimesis 5Dokumen10 halamanA (1) - Kapui Mimesis 5Erlinda NovitaniaBelum ada peringkat
- AppendicesDokumen20 halamanAppendicesKhanafi KhanafiBelum ada peringkat
- NewDokumen5 halamanNewRaymundus BerafBelum ada peringkat
- Zamrud Khatulistiwa PDFDokumen186 halamanZamrud Khatulistiwa PDFYeti HermitaBelum ada peringkat
- P-4.Contoh Biografi PengarangDokumen17 halamanP-4.Contoh Biografi PengarangZalfa AinissifaBelum ada peringkat
- Kelompok 1 Sejarah SastraDokumen7 halamanKelompok 1 Sejarah SastraNadjwa Salshabilla HumayraBelum ada peringkat
- Mingguraya, ASA, Dan SastraDokumen5 halamanMingguraya, ASA, Dan SastraSainul HermawanBelum ada peringkat
- Bahasa Puisi Dan Tanggung Jawab PenyairDokumen5 halamanBahasa Puisi Dan Tanggung Jawab PenyairSyaif MuhamadBelum ada peringkat
- S IND 1103252 Chapter1Dokumen10 halamanS IND 1103252 Chapter1Putra Aditya PradanaBelum ada peringkat
- KALAM 25 Arif B. PrasetyoDokumen39 halamanKALAM 25 Arif B. PrasetyoAtiqurrahman BakrieBelum ada peringkat
- Perdebatan Sastra KontekstualDokumen5 halamanPerdebatan Sastra KontekstualniroelBelum ada peringkat
- DENNY JA - Memotret Batin Dan Isu Sosial Melalui Puisi Esai PDFDokumen250 halamanDENNY JA - Memotret Batin Dan Isu Sosial Melalui Puisi Esai PDFYoyon SugiyonoBelum ada peringkat
- Artikel Jurnal Adab MuqaranDokumen15 halamanArtikel Jurnal Adab MuqaranPink DigitalBelum ada peringkat
- Puisi MochtarDokumen5 halamanPuisi MochtarAmin MudzakkirBelum ada peringkat
- Midah, Simanis Bergigi Emas Karya PramoedyaDokumen28 halamanMidah, Simanis Bergigi Emas Karya PramoedyaSanusi Sunawar Heri MurtiBelum ada peringkat
- ID Tema Puisi Indonesia Modern Periode AwalDokumen10 halamanID Tema Puisi Indonesia Modern Periode AwalAnonymous 2o9xL8VGGBelum ada peringkat