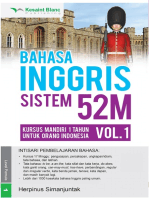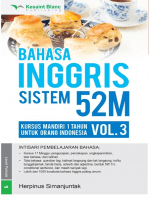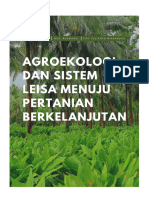SSRN Id3431495
SSRN Id3431495
Diunggah oleh
Yesi LismawatiJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
SSRN Id3431495
SSRN Id3431495
Diunggah oleh
Yesi LismawatiHak Cipta:
Format Tersedia
Manajemen Agribisnis
Sebuah pengantar
IR. SRI HINDARTI, Msi
Universitas Islam Malang
Dan
DR.IR.DYANASARI, MBA
Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
KATA PENGANTAR
Buku Manajemen Agribisnis - Sebuah Pengantar, merupakan salah satu dari
banyak buku tentang Manajemen Agribisnis di Indonesia, yang diterbitkan untuk
memberi masukan pada mahasiswa jurusan Agribisnis. Buku ini akan dilengkapi
dengan pedoman-pedoman lainnya yang sarat dengan perkembangan informasi
terbaru, namun karena keterbatasan waktu, untuk sementara buku ini terbit.
Disadari bahwa kekurangan yang banyak terjadi, terutama dalam bab manajemen
keuangan, manajemen biaya, yang akan dilengkapi kemudian.
Kritik dan saran perbaikan akan diterima dengan tangan terbuka.
Penulis
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
DAFTAR ISI
Manajemen Agribisnis ........................................................................................................ 1
Sebuah pengantar ............................................................................................................... 1
DAFTAR ISI........................................................................................................................... 2
DAFTAR TABEL .................................................................................................................... 5
DAFTAR GAMBAR................................................................................................................ 6
INDEKS................................................................................................................................. 7
GLOSSARIUM.........................................................................Error! Bookmark not defined.
I. PENDAHULUAN ................................................................................................................ 9
1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Agribisnis ............................................................. 11
1.2. Mengapa perlu mempelajari Manajemen Agribisnis............................................ 13
1.3. Manfaat mempelajari Manajemen Agribisnis ....................................................... 16
1.4. Tujuan Mempelajari Manajemen Agribisnis ........................................................ 16
II. DASAR-DASAR AGRIBISNIS ............................................................................................ 20
2.1. Dasar agribisnis adalah bisnis ................................................................................ 20
2.2. Hukum/Aturan Bisnis ............................................................................................. 23
2.2.1. Cara membuat Aturan Bisnis .............................................................................. 24
2.2.2. Metodologi Aturan Bisnis ................................................................................... 26
2.2.3. Kategori Aturan Bisnis ......................................................................................... 26
III. FUNGSI MANAJEMEN DALAM AGRIBISNIS .................................................................. 28
3.1. Perencanaan merupakan fungsi pertama ............................................................. 30
3.3. Fungsi Kedua : Mengatur ...................................................................................... 31
3.3. Fungsi ketiga : Memimpin ..................................................................................... 32
3. 4. Fungsi Kontrol Manajemen ................................................................................... 33
3.4.1. Mengapa Kontrol Dibutuhkan? ........................................................... 36
3.4.2. Perlunya Kontrol / Pengendalian yang Baik ....................................... 37
3.4.3. Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Pertanian.................................. 39
IV. KEKHUSUSAN MANAJEMEN AGRIBISNIS ..................................................................... 45
4.1. Banyaknya Faktor yang Berpengaruh dalam Agribisnis ......................................... 45
4.2 Pentingnya Pengetahuan Dalam Agribisnis ......................................................... 48
4.3. Menentukan Produk Pertanian yang dipilih .......................................................... 51
4.4. Menerima Syarat-syarat dan Ketentuan yang Berlaku ......................................... 52
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
4.5. Syarat Pertanian Organik ....................................................................................... 54
4.6. Mengutamakan Agribisnis yang Berwawasan Lingkungan .................................... 63
V. PENTINGNYA SUMBERDAYA MANUSIA DALAM AGRIBISNIS ................................... 80
VI. AGROBISNIS DI INDONESIA ........................................................................................ 81
6.1. Minyak Kelapa Sawit .............................................................................................. 87
6.1.1 Kebijakan Pajak Ekspor Minyak Sawit Indonesia ............................. 96
6.1.2 Isu-Isu Lingkungan Hidup Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia .. 98
6.1.3. Moratorium Mengenai Konsesi Baru Hutan Perawan ...................... 99
6.1.4. Prospek Masa Depan Industri Minyak Sawit di Indonesia ............... 99
6.2 Masalah yang dihadapi oleh Agribisnis Indonesia ............................................. 100
(20) Penggunaan lahan yang belum maksimal ......................................................... 103
(21) Perkebunan yang belum Maksimal .................................................................... 104
6.3 Pertanian/Agribisnis di Negara Maju ................................................................. 106
6.4. Solusi dalam Pengembangan Agribisnis Indonesia ............................................. 107
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... 126
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Pertumbuhan Sektor Pertanian (%) ........................................................ 86
Tabel 3. Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia, 2008-2016 ...... 94
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. . Logo Sertifikasi Organik .................................................................. 61
Gambar 2. Jumlah Tanaman Kelapa Sawit (ha) dan Produksinya (ribuan ton) ... 88
Gambar 3. Perkebunan kelapa sawit dari hutan asli yang ditebangi di Riau,
Indonesia. .............................................................................................................. 90
Gambar 4. Produksi Kelapa Sawit di Sumatera dan Kalimantan......................... 95
Gambar 5. Pemilik Kelapa Sawit di Indonesia .................................................... 96
Gambar 7. Persentase Penggunaan Lahan di Indonesia, 1999 ........................... 103
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
INDEKS
(controlling, 19 Supply Chain Management, 65, 119
(minimum crop requirement, 57, 73 value – added, 49
A Concept of Agribusiness, 8 value-added, 45
actuating), 19
asimetri informasi, 45
bargaining power, 14
biofuel,, 17
distribusi pangan, 8, 64
efek allelopati, 57, 74
elastis, 14
Eucalyptus spp., 57
fungsi kontrol kritis manajemen, 34
Hot Money), 45
interdependensi, 15
International Federation of Organik
Agriculture Movements, 53
John Davis, 9
Komite Akreditasi Nasional (KAN), 53
lag, 14
Lembaga Sertifikasi Organik (LSO)., 53
logo organik, 59
low-holding-backhence, 13
Manajemen agribisnis, 6, 8
manajemen rantai pasok, 64
meningkatkan industri pertanian dan
produksi pertanian., 16
Net Promoter Score, 39
Organizing, 27, 126
organizing), 19
Pertanian organik, 53, 56, 73
planning, 19
Planning, 27, 126
praktik bisnis, 23
rantai nilai tambah, 8
rantai produksi, 15
RAROC, 39
Ray A. Goldberg, 8
risk-adjusted return of capital, 39
Sertifikasi Organik, 53, 60, 127
Sistem pangan, 16
Standard of Operasional Procedure, 26
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
GLOSSARIUM
HACCP adalah sistem manajemen di mana keamanan pangan ditangani melalui
analisis dan dilakukan pengendalian bahaya biologis, kimia, dan fisik dari
produksi bahan mentah, pengadaan dan penanganan, hingga manufaktur,
distribusi dan konsumsi produk jadi ( FDA, 2018).
Manajemen agribisnis adalah manajemen yang berfokus pada sistem bisnis dan
fungsi manajerial yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan pada seluruh
sektor agribisnis
Konsep agribisnis adalah konsep usaha pertanian yang merujuk kepada
perusahaan pertanian yang sukses dengan melihat kepada kebutuhan masyarakat
dan bukan hanya menghasilkan uang
Pendidikan manajemen agribisnis merupakan suatu kualifikasi yang mampu
membentuk personel menjadi manajer yang baik yang memiliki keahlian
manajerial.
Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar (doing
things right). Hal ini merupakan konsep maternatik, yang merupakan
perhitungan ratio antara keluaran (output) dan masukan (input).
Sertifikasi organik adalah serangkaian kegiatan pertanian organik yang telah
memenuhi standar yang dipersyaratkan tentang Sistem Pangan Organik.
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
I. PENDAHULUAN
Manajemen agribisnis adalah manajemen yang berfokus pada sistem
bisnis dan fungsi manajerial yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan pada
seluruh sektor agribisnis.
Manajemen agribisnis membahas banyak hal, tidak saja segi manajemen,
namun juga distribusi pangan, mesin pertanian, pengolahan, pemuliaan, produksi
tanaman, dan pasokan benih, serta pemasaran dan penjualan ritel. Semua agen
rantai makanan dan lembaga-lembaga yang berkaitan dalam sistem merupakan
bagian dari sistem agribisnis. Pengertian ini sama saat pertama kali Ray A.
Goldberg menciptakan istilah agribisnis bersama dengan rekan penulis John H.
Davis dalam buku mereka yang berjudul A Concept of Agribusiness , Boston:
Divisi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Administrasi Bisnis, Universitas Harvard,
1957) (Ward, 2017). Buku itu menelusuri rantai nilai tambah yang kompleks yang
dimulai dengan pembelian benih dan ternak oleh petani dan diakhiri dengan
produk yang cocok untuk konsumen. Ray A. Goldberg, seorang dosen Ekonomi
Harvard Business School, pada saat itu sudah memikirkan ekosistem dan
pemangku kepentingan serta memikirkan sebuah kata yang paling tepat di akhir
1950-an ketika dia mencoba menemukan cara untuk menggambarkan bisnis
pertanian secara keseluruhan : cara bertani dan bisnis yang tumpang tindih,
didalamnya terdapat apa yang disebut sistem makanan. Menurut Goldberg,
pengertian agribisnis adalah sebuah bisnis yang semua orang terlibat di dalamnya,
dari teknologi sampai ke konsumen. Tahun 2017 menandai 60 tahun sejak
Goldberg menciptakan istilah agribisnis, kemudian didefinisikan sebagai
"interdependensi tumbuh pertanian dan industri yang memasok pertanian, dan
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
proses berlanjut kepada mendistribusikan produk pertanian (Ward, 2017), Jadi
menurut Goldberg, agribisnis, tidak saja berarti bisnis besar, bisnis kecil pun di
sektor pertanian disebut sebagai agribisnis, apakah itu menguntungkan atau tidak ,
sepanjang itu mencakup semua aspek sistem pangan, disebut sebagai agribisnis
(Ward, 2017).
Menurut Ward(2017), konsep agribisnis yang tercipta pada 1957 itu,
memang dicetuskan oleh Goldberg dan John Davis ( yang saat itu menjabat
sebagai direktur Program Pertanian dan Bisnis). Keduanya mendiskusikan fungsi
pertanian yang saling berkaitan sehingga pertanian dan industri dapat
menghasilkan makanan dan serat secara lebih efisien (Ward, 2017). .Menurut
Goldberg dan Davis, konsep agribisnis merujuk kepada perusahaan yang sukses
dengan melihat kepada kebutuhan masyarakat dan bukan hanya menghasilkan
uang (Ward, 2017). Selanjutnya dikatakan bahwa setiap pengambil keputusan
dalam sistem pangan terlibat dalam kebijakan privat, publik dan bukan-untuk-
keuntungan semata dan hal itu penting karena sistem pangan lebih bermanfaat
bagi masyarakat daripada sistem lainnya (Ward, 2017).
Sejak semula Goldberg berfokus kepada kebijakan pangan dan agribisnis
serta iklim dan dampaknya pada sistem pangan global (Ward, 2017). Goldberg
telah berjasa di seluruh dunia dalam kebijakan pangan dan agribisnis, muali dari
Costta Rica hingga ke Filipina, ke Polandia, Israel, Bank Dunia, dan Royal
Agricultural College Inggris (Ward, 2017). Goldberg telah mengajar agribisnis
selama lebih dari 60 tahun. Adapun agribisnis selama waktu itu, Goldberg
mengatakan perubahan terbesar selama ini dalam agribisnis adalah teknologi.
Selain itu, perubahan terbesar adalah kemajuan ilmiah yang memungkinkan
10
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
manusia memahami bagaimana tumbuhan dan hewan dan manusia semua
berinteraksi, untuk berpengetahuan tentang nutrisi dan kesehatan mental serta
fisik.
Goldberg menemukan bahwa dalam pengertian agribisnis, terdapat
revolusi baru dalam sistem pangan (Ward, 2017). Goldberg juga mengingatkan
bahwa salah satu fokus utama adalah untuk selalu melihat hubungan antara
aspek teknis, ekonomi, lingkungan dan manusia dalam pertanian dan, yang paling
penting, adalah tentang kemampuan menyatukan orang (Ward, 2017).
Namun demikian, banyak orang tidak menyadari seberapa banyak mereka
terhubung satu sama lain dan bekerja sama dalam sistem pangan bersama.
Goldberg telah memberi kontribusi terbesar yang dapat diberikan untuk pertanian
kepada dunia, bahwa untuk memahami . demi pangan,, semua manusia bisa
bekerja bersama(Ward, 2017).
1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Agribisnis
Dalam industri pertanian, "agribisnis" digunakan sebagian orang hanya
sebagai “pelabuhan” pertanian dan bisnis. Padahal industri pertanian mengacu
pada berbagai kegiatan dan disiplin yang dicakup oleh produksi pangan mulai
konvensional hingga modern. Dalam manajemen agribisnis, akan dibahas tentang
manajemen agribisnis yang umumnya terjadi, dalam skala kecil hingga industri,
terutama menuju kepada tujuan pokok dalam agribisnis, yakni ketahanan pangan
dan menuju usaha pertanian yang efisien.
Menurut etimologi, istilah agribisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu
Agriculture dan Bussines yang artinya bisnis pertanian. Banyak orang
11
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
mengartikan agribisnis sebagai usaha pertanian secara modern. Pengertian secara
konsepsual lebih luas dan dinamis.
Downey dan Erickson (1987) membagi agribisnis menjadi 3 sektor, yaitu
(1) sektor masukan (input); (2) sektor produksi (farm) dan sektor keluaran
(output). Sektor masukan adalah menyediakan perbekalan kepeda para pengusaha
tani (petani) untuk dapat memproduksi hasil tanaman dan ternak. Termasuk dalam
sektor ini adalah bibit, pupuk, makanan ternak, bahan kimia, mesin pertanian,
bahan bakar, dan lainnya. Sektor produksi usahatani memproduksi hasil tanaman
dan ternak yang diproses dan disebarkan kepada konsumen akhir oleh sektor
keluaran (output).
Definisi agribisnis secara umum dibagi menjadi 2, secara sempit dan
secara luas. Secara sempit (tradisonal) agribisnis menunjuk pada produsen hasil
pertanian dan secara luas, agribisnis menunjuk kepada pengusaha pembuat bahan
masukan /input seperti penyalur bahan kimia, pupuk buatan, dan mesin-mesin
pertanian, pembuatan benih dan makanan ternak, dan lembaga yang melayani
produksi pertanian lainnya. Sementara definisi yang lain dikutipkan adalah dari
Davis dan Golberg mendefinisikan agribisnis sebagai seluruh kegiatan yang
meliputi pembuatan dan pendistribusian kebutuhan pertanian, kegiatan produksi
pertanian, penyimpanan dan pengolahan dan distribusi hasil pertanian dan hasil
olahannya. Definisi ini menunjuk pada kegiatan yang lebih luas bukan hanya
produksi pertanian saja tetapi termasuk penyediaan input dan pemasaran hasil
pertanian dan seterusnya.
Oleh karenanya, definisi agribisnis modern yang sudah disepakati umum
adalah usaha dalam bidang pertanian yang meliputi seluruh sektor bahan masukan
12
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(input) pertanian, usahatani, produk yang memasok bahan masukan usahatani,
produk yang terlibat dalam produksi pertanian, menangani pemrosesan hasil
pertanian, dan pemasaran hasil pertanian. Dalam hal ini agribisnis diartikan
sebagai semua kegiatan di sektor pertanian dimulai dengan pengadaan dan
penyaluran sarana produksi (the manufacture and distribution of farm supplies),
proses produksi usahatani (production on the farm), penanganan pasca
panen/pengolahan, dan pemasaran (marketing) hingga produk pertanian/makanan
tersebut sampai kepada konsumen. Jika digambarkan dalam skema, sebagaimana
berikut ini :
Agribisnis
Penyediaan Usahatani Penanganan Distribusi
Input (Produksi Pasca Dan
Dan komoditi Panen dan Pemasaran
Sarana Produksi Pertanian) Pengolahan
Gambar 1. Arti dan Ruang Lingkup Agribisnis
Sumber : Hindarti, 2019
1.2. Mengapa perlu mempelajari Manajemen Agribisnis
Pendidikan agribisnis berguna bagi seseorang yang ingin berkecimpung
dalam dunia agribisnis. Sebagai negara berbasis pertanian, Indonesia
membutuhkan tenaga – tenaga terdidik yang memahami manajemen agribisnis,
karena manajemen agribisnis memang berbeda dengan menajeman produk yang
bukan agribisnis. Hal ini disebabkan karena karakter produk agribisnis yang
13
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
memang tidak sama dengan produk lain.. Myanka (2018) memerinci karakteristik
produk pertanian sebagai berikut :
1. Produk pertanian cenderung besar dan berat serta volumenya kadang-kadang
sangat besar dibanding nilainya. Hal ini terutama jika dibandingkan dengan
barang yang bukan pertanian.
2. Permintaan atas fasilitas penyimpanan dan transportasi lebih tinggi dan lebih
khusus dibandingkan dengan produk selain pertanian,
3. Komoditi pertanian relatif tidak bertahan lama daripada barang-barang yang
bukan pertanian.
4. Komoditi pertanian tergantung musim, seperti mangga, jambu, belimbing,
rambutan, anggur, dan lain-lain, hanya tersedia pada saat musimnya masing-
masing.
5. Produk pertanian ditemukan tersebar di wilayah geografis yang luas dan
karena itu pengumpulannya merupakan masalah yang serius. Sebagai contoh,
areal tanam padi terletak bukan pada sebidang tanah yang luas, namun terpisah-
pisah. Akibatnya saat panen, memerlukan transportasi untuk mengumpulkan hasil
panen. Demikian pula, jika memanen kacang mete, misalnya. Letak pohon jambu
mente terpisah dengan jarak yang cukup jauh, apalagi pada perkebunan rakyat..
6. Masa panen yang berbeda, hanya karena varietas dan jenis tanaman yang
berbeda. Hal ini disebabkan karena masa panen yang tidak sama dan tidak bisa
dibuat sama meski jenis tanaman sama dengan varietas berbeda.
7. .Profil terutama di negara-negara berkembang, hasil pertanian memiliki low-
holding-backhence yakni kecenderungan menjual produk segera setelah panen
dengan harga berapa pun mereka dapat.
14
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
8. Permintaan dan penawaran hasil pertanian hampir selalu bersifat elastis, yang
hal ini terutama disebabkan oleh lag dalam produksi, sehingga setiap keuntungan
yang dihasilkan diambil oleh perantara.
Artinya, mereka tidak mempunyai posisi tawar yang baik atau tidak mempunyai
bargaining power. Sifat elastis ini ditunjukkan oleh sifat responsif dari adanya
sedikit perubahan harga terhadap permintaan dan penawaran produk pertanian.
Karakter produk pertanian lainnya diuraikan oleh Anonymousb (2018)
sbb. :
1. Hasil produk yang tidak seragam : Dalam satu pohon jeruk, misalnya,
menghasilkan jeruk yang tidak hanya tidak sama besarnya, namun kadang-kadang
rasanya pun tidak semua manis. Hal ini kadang-kadang menyulitkan dalam
pemasaran produk pertanian. Sortasi dan standardisasi menjadi solusinya.
2. Sulitnya melakukan panen yang benar dan tepat : Karena karakteristik biologis
dan fisioplogis, maka pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu,
kandungan air dari saat panen kadang-kadang masih terlalu tinggi sehingga
dibutuhkan pengeringan sebelum disimpan, yang jika tidak dilakukan, akan
mudah membusuk.
3. Membutuhkan fasilitas penyimpanan khusus : Pada produk-produk buah-
buahan, dibutuhkan tempat penyimpanan dengan suhu udara tertentu agar buah
tidak cepat busuk
4. Membutuhkan pengolahan lebih lanjut agar produk dapat lebih awet, sebagai
contoh pisang yang diolah menjadi keripik.
5. Sifat produk yang musiman, artinya tidak setiap saat produk tersebut dihasilkan
atau hasil produksinya akan diperoleh pada waktu-waktu tertentu. Sifat ini
15
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
menyebabkan ketidakstabilan harga produk tertentu di pasaran, yang kadang-
kadang berharga tinggi saat produk tersebut langka dan terkadang juga sangat
rendah karena panen yang melimpah.
6. Letak produk berada jauh dari konsumen : Hasil pertanian umumnya berada di
pedesaan karena mayoritas memang ditanam di wilayah pedesaan. Padahal
mayoritas konsumennya ada di daerah perkotaan.
1.3. Manfaat mempelajari Manajemen Agribisnis
Manfaat mempelajari Manajemen Agribisnis :
(1) Mengetahui perkembangan mutakhir dalam agribisnis, perdagangan
agribisnis, publikasi agribisnis, dan seterusnya, yang sudah dan sedang
dilakukan di seluruh dunia. Oleh karenanya, masing-masing elemen produksi
dan distribusi pertanian yang dapat digambarkan sebagai agribisnis,
hendaknya dimengerti dengan baik.
(2) Mengetahui "interdependensi" dari berbagai sektor dalam rantai produksi,
yang sebenarnya saling berkaitan.
(3) Mengetahui praktik bisnis dalam sektor pertanian termasuk industri pertanian
1.4. Tujuan Mempelajari Manajemen Agribisnis
(1) Agar sektor pertanian termasuk industri dan produksi pertanian dapat
meningkat
(2) Agar dapat mengetahui bagaimana meningkatkan kegiatan di sektor
pertanian dalam upaya untuk meningkatkan industri pertanian dan produksi
pertanian.
16
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(3) Agar dapat menerapkan teori dan praktik bisnis ke industri pertanian
untuk menurunkan biaya, meningkatkan keuntungan dan memastikan
bahwa pertanian atau produk pertanian dapat didistribusikan secara efektif.
(4) Agar dapat memahami bidang agribisnis yang meliputi : sistem pangan
dalam bidang pertanian, komoditi dan pemasaran produk pertanian ,
pengetahuan dalam menunjang kemampuan dalam agribisnis, manajemen
menyeluruh dalam agribisnis, mengelola tenaga kerja, masalah pangan
nasional dan global, dan lain lain.
(5) agar mahasiswa dan masyarakat luas yang mempelajari manajemen
agribisnis dapat memahami manajemen agribisnis dengan baik. Hal ini
berkaitan dengan kemampuan dan keahlian yang saat ini terus dibutuhkan.
Bahkan di negara maju seperti AS, disebutkan bahwa Departemen Pertanian
AS memperkirakan kekurangan karyawan yang memenuhi syarat untuk
mengisi posisi manajer agribisnis termasuk bisnis dan keuangan khusus serta
perwakilan pemasaran / penjualan. Sebagaimana diketahui, AS mempunyai
hasil pertanian terbesar di dunia yang harus dipasarkan ke seluruh dunia
(diekspor). Dalam posisi tersebut, dibutuhkan kemampuan seseorang untuk
menyelami fungsi pedagang komoditi, pengelola lingkungan dalam
perusahaan sebaik sebagaimana pemilik atau pengelola kebun. Mereka yang
mempelajari Manajemen Agribisnis tidak cukup mempelajari hal-hal tersebut
di atas, namun mereka juga harus dapat menganalisa kondisi keuangan,
mengelola industri produk pertanian, bahkan memahami peran Manajer
pemasaran / periklanan, Manajer Hubungan Masyarakat serta Manager
Penjualan.
17
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Dengan mempelajari manajemen agribisnis, maka bidang pengelolaan
sumber daya alam, industri pertanian di perusahaan energi atau biofuels, produk
makanan, mesin pertanian, benih, pakan ternak, dan lain-lain termasuk jasa
keuangan/ kredit untuk pertanian, konsultan agribisnis, inspektur wilayah
pertanian, manajer program pertanian, analis kebijakan, pengawas produksi,
asosiasi penjualan, dan pelobi/negosiator, dapat terlaksana dengan baik. Hal ini
ditunjukkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) memperkirakan peluang
kerja bagi analis keuangan agribisnis akan meningkat 16% antara 2012 dan 2022
(Bureau Labor of Statistics, 2018).
(4) Dapat meningkatkan pengetahuan sebagai manajer pertanian yang handal,
menangani tugas yang diemban tidak hanya mengawasi operasi sehari-hari , baik
di sebuah peternakan atau situs pertanian atas nama petani, perusahaan atau
industri pertanian, maupun operasional usaha pertanian kecil yang mungkin hanya
mempekerjakan seorang manajer tunggal, atau pun operasi besar yang mungkin
mempekerjakan beberapa manajer yang mengawasi area khusus, seperti bisnis
atau pemasaran. Dengan demikian, usaha yang dikelolanya dapat efisien.
(5) Dapat menangani agribisnis dengan memperhatikan dampak rendah kepada
lingkungan dan memberi kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan.
Sebagai contoh, produsen benih dan agribisnis seperti Dow AgroSciences,
DuPont, Monsanto, dan Syngenta; AB Agri (bagian dari Associated British
Foods), pakan ternak, biofuel, transportasi bidang pertanian dan pengolahan
biji-bijian; John Deere ( produsen mesin pertanian), Ocean Spray, koperasi
petani; dan Purina Farms, pertanian agritourism, adalah merupakan bagian
18
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
dari agribisnis, semua perusahaan tersebut di atas memperhatikan
pembangunan pertanian secara berkelanjutan.
(6) Agar dapat mempromosikan lebih banyak pembangunan ekonomi pangan,
yang melibatkan banyak lembaga pemerintah yang didukung oleh penelitian
dan publikasi studi dan laporan ekonomi yang mengeksplorasi praktik
agribisnis. Lembaga-lembaga tersebut berfokus kepada makanan yang
diproduksi untuk ekspor, termasuk Departemen Pertanian AS, Agri-food
Kanada (AAFC), Austrade, dan Perdagangan dan Perusahaan Selandia Baru
(NZTE). Sebagai contoh, Federasi Asosiasi Perdagangan Internasional
menerbitkan studi dan laporan oleh FAS dan AAFC.
19
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
II. DASAR-DASAR AGRIBISNIS
Hal yang perlu diketahui adalah dasar- dasar bisnis pertanian agar dalam
bahasan berikutnya, materi yang disajikan dapat lebih mudah
dipahami.
2.1. Dasar agribisnis adalah bisnis
Karena dasar dari agribisnis adalah bisnis, maka hal yang perlu diketahui
adalah bisnis itu sebenarnya. Dalam sebuah usaha atau bisnis, maka terdapat
bagian-bagian penting dari bisnis itu :
1. Hukum Bisnis./ perusahaan
2. Administrasi Bisnis
3. Manajemen suatu bisnis: Akuntansi, Entitas bisnis , tata kelola perusahaan
: perencanaan (planning), pengelolaan (organizing), pelaksanaan (actuating) dan
mengontrol/evaluasi (controlling)
4. Pengetahuan tentang kondisi ekonomi
5. Pengetahuan tentang keuangan
6. Pengetahuan tentang pemasaran
7. Pengetahuan tentang Manajemen
8. Pengetahuan tentang Organisasi
9. Pengetahuan tentang Pameran
Bisnis adalah kegiatan menghasilkan uang dengan memproduksi atau
membeli dan menjual produk (barang dan jasa). Dengan kata lain, "aktivitas atau
usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.
20
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Bisnis itu dapat berupa perusahaan sendiri, kemitraan, atau memiliki
organisasi formal, tetapi tetap berkisar dari pedagang kaki lima hingga ke
perusahaan terbuka.
Siapa pun yang menjalankan aktivitas yang menghasilkan laba adalah
menjalankan bisnis, Pemilik bisnis bertanggung jawab atas semua hutang yang
dikeluarkan oleh bisnis.. Pemilik secara pribadi dikenakan pajak atas semua
pendapatan dari bisnis.
Sebuah perusahaan adalah badan hukum yang mempunyai kewajiban
terbatas harus menyetor pajak perusahaan senbagiaman yang telah diatur
pemerintah di negara itu.
Bentuk kepemilikan bisnis berbeda menurut yurisdiksi, yang umumnya
dibagi sbb:
1. Kepemilikan tunggal:
Kepemilikan tunggal, juga dikenal sebagai pedagang tunggal, dimiliki oleh satu
orang dan beroperasi untuk keuntungan mereka. Pemilik mengoperasikan bisnis
sendiri dan dapat mempekerjakan karyawan. Seorang pemilik tunggal memiliki
kewajiban tidak terbatas untuk semua kewajiban yang dikeluarkan oleh bisnis,
baik dari biaya operasi atau penilaian terhadap bisnis. Semua aset bisnis milik
pemilik tunggal, termasuk, misalnya, infrastruktur komputer, inventaris apa pun,
peralatan manufaktur, atau perlengkapan ritel, serta setiap properti nyata yang
dimiliki oleh pemilik tunggal.
2. Kemitraan:
Kemitraan adalah bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dalam sebagian
besar bentuk kemitraan, masing-masing mitra memiliki kewajiban tidak terbatas
21
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
untuk utang yang dikeluarkan oleh bisnis. Tiga jenis kemitraan nirlaba yang
paling umum adalah: kemitraan umum, kemitraan terbatas, dan kemitraan
tanggung jawab terbatas
3. Korporasi:
Pemilik perusahaan memiliki kewajiban terbatas dan bisnis memiliki kepribadian
hukum yang terpisah dari pemiliknya. Korporasi dapat berupa milik pemerintah
atau milik pribadi. Mereka dapat mengatur baik untuk keuntungan atau sebagai
organisasi nirlaba. Sebuah perusahaan nirlaba milik swasta dimiliki oleh para
pemegang sahamnya, yang memilih dewan direksi untuk mengarahkan
perusahaan dan mempekerjakan staf manajerialnya. Perusahaan nirlaba yang
dimiliki secara pribadi dapat secara pribadi dipegang oleh sekelompok kecil
individu, atau dimiliki publik, dengan saham yang diperdagangkan secara publik
yang terdaftar di bursa saham.
4. Koperasi:
Koperasi berasal dari kata "co-op" yang artinya bekerjasama.
Koperasi adalah bisnis dengan kewajiban terbatas yang dapat mengatur sebagai
laba atau tidak untuk mencari keuntungan. Sebuah koperasi berbeda dari sebuah
perusahaan karena memiliki anggota, bukan pemegang saham, dan mereka
berbagi otoritas pengambilan keputusan. Koperasi biasanya diklasifikasikan
sebagai koperasi konsumen atau koperasi pekerja. Koperasi sangat penting bagi
ideologi demokrasi ekonomi.
5. Perseroan terbatas atau PT :
PT adalah kemitraan dengan tanggung jawab terbatas, dan jenis organisasi bisnis
tertentu lainnya melindungi pemilik atau pemegang saham mereka dari kegagalan
22
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
bisnis dengan melakukan bisnis di bawah badan hukum yang terpisah dengan
perlindungan hukum tertentu. Sebaliknya, bisnis tidak berhubungan atau orang
yang bekerja sendiri biasanya tidak dilindungi.
2.2. Hukum/Aturan Bisnis
Bisnis mempunyai aturan yang dikenal sebagai Aturan bisnis adalah
aturan yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek bisnis dan selalu
menyelesaikan baik benar atau salah. Aturan bisnis dimaksudkan untuk
menegaskan struktur bisnis atau untuk mengendalikan atau mempengaruhi
perilaku bisnis. Aturan bisnis menggambarkan operasi, definisi dan batasan yang
berlaku untuk suatu organisasi. Aturan bisnis dapat berlaku untuk orang, proses,
perilaku perusahaan dan sistem komputasi dalam suatu organisasi, dan
ditempatkan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.
Misalnya, aturan bisnis mungkin menyatakan bahwa tidak ada pemeriksaan
hutang yang harus dilunasi sebelum pelanggan yang sama melakukan pembelian
lagi. Dalam kenyataannya, banyak pelanggan yang belum membayar pada saat
barang telah diserahkan dan dia membeli kembali. Contoh lain dari aturan bisnis
adalah melarang penyewa menyewakan kembali tempat yang disewanya, atau
penyewa harus membayar kewajiban membayar sewa tepat waktu dan jika tidak
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 persen per hari, dan lain
sebagainya.
Meskipun aturan bisnis mungkin informal atau bahkan tidak tertulis,
namun alangkah baiknya untuk mendokumentasikan aturan dengan jelas dan
memastikan bahwa tidak akan terjadi konflik. Hal ini merupakan aktivitas
kegiatan yang berharga. Ketika sebuah perusahaan agribinsi dikelola dengan hati-
23
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
hati, aturan dapat digunakan untuk membantu organisasi itu dapat mencapai
tujuan dengan lebih baik, menghapus hambatan agar terjadi pertumbuhan pasar,
mengurangi kesalahan yang berbiaya mahal, meningkatkan komunikasi,
mematuhi persyaratan hukum, dan meningkatkan loyalitas pelanggan.
2.2.1. Cara membuat Aturan Bisnis
Aturan bisnis merupakan aturan yang menunjukkan sebuah perusahaan
atau organisasi yang dikelola tersebut dijalankan secara detil, sementara adanya
strategi perusahaan atau organisasi menunjukkan bahwa bisnis tersebut berfokus
kepada bisnis pada tingkat mikro atau makro untuk mengoptimalkan hasil.
Menunjukkan strategi perusahaan merupakan pemberian arah kepada tingkat yang
lebih tinggi tentang apa yang harus dilakukan oleh organisasi. Aturan bisnis
memberikan panduan rinci tentang bagaimana strategi dapat diterjemahkan
menjadi tindakan.
Adanya aturan bisnis dari sebuah perusahaan atau organisasi yang tertulis,
merupakan kegiatan yang bermanfaat, apalagi setelah dibicarakan atau bahkan
sudah menjadi bagian dari kesadaran berorganisasi. Kini kegiatan itu telah
menjadi praktik yang cukup umum bagi organisasi untuk mempunyai aturan
bisnis.
Perusahaan atau organisasi dapat memilih untuk secara proaktif
mendeskripsikan praktik bisnis mereka dan menghasilkan basis data berdasarkan
aturan yang diciptakannya. Meskipun kegiatan ini mungkin berbiaya mahal dan
memakan waktu, namun bermanfaat bagi kemajuan perusahaan dan organisasi di
masa depan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menyewa konsultan untuk
menyisir setiap kegiatan dalam perusahaan atau organisasi untuk
24
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
mendokumentasikan dan mengkonsolidasikan berbagai standar dan metode yang
saat ini dijalankan/dipraktikkan/diimplementasikan.
Kegiatan mengumpulkan aturan bisnis juga merupakan kegiatan “panen”,
bahkan “menambang” aturan bisnis. Analis bisnis atau konsultan kemudian dapat
mengekstrak aturan dari dokumentasi IT (seperti kasus penggunaan, spesifikasi
atau kode sistem). Perusahaan atau organisasi juga dapat menyelenggarakan
lokakarya dan wawancara dengan para ahli dalam bidang yang menjadi
kompetensi masing-masing. Penggunaan teknologi perangkat lunak dapat
dirancang untuk merekam aturan bisnis melalui analisis kode atau perilaku
pengguna yang sebenarnya dapat mempercepat pemrosesan pengumpulan aturan
bisnis.
Kini, aturan bisnis telah berlaku secara umum dan didokumentasikan
secara informal selama tahap awal proyek pembuatan aturan bisnis. Cara
mengumpulkan aturan bisnis dapat dilakukan dengan 2 cara :
1. Insindental. Dalam hal ini pengumpulan aturan bisnis bersifat incidental,
seperti akan dilakukan peluncuran produk baru atau rekayasa ulang dari proses
yang kompleks, baru dibuat definisi aturan bisnis baru. Praktik pengumpulan
aturan bisnis yang insidental dapat menjadi rentan menjadi aturan bisnis yang
tidak konsisten atau bahkan bertentangan dalam unit organisasi yang berbeda,
atau dalam unit organisasi yang sama dari waktu ke waktu. Inkonsistensi ini akan
menciptakan masalah yang sulit ditemukan dan diperbaiki.
2. Dirancang di awal waktu
Pembuatan aturan bisnis untuk didokumentasikan akan menjadi aturan
bisnis yang berbiaya lebih murah dan lebih mudah dicapai daripada cara pertama
25
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
2.2.2. Metodologi Aturan Bisnis
Untuk mencari cara terbaik dalam mengumpulkan dan
mendokumentasikan aturan bisnis, para ahli dalam analisis bisnis telah membuat
Metodologi Aturan Bisnis. Metodologi ini mendefinisikan proses membuat aturan
bisnis dalam bahasa alami, dengan cara yang dapat diverifikasi dan dimengerti.
Proses ini tidak sulit untuk dipelajari, dapat dilakukan secara real-time, dan
memberdayakan para pemangku kepentingan bisnis untuk mengelola aturan bisnis
mereka sendiri secara konsisten.
2.2.3. Kategori Aturan Bisnis
1. Media bahasa yang digunakan
Elemen paling dasar dari aturan bisnis adalah bahasa yang digunakan
untuk mengekspresikannya. Pemilihan media bahasa Inggris dapat membawa
suasana kepada percepatan kemajuan perusahaan yang mengarah kepada ekspor,
misalnya.
2. Menetapkan Definisi
Menetapkan definisi dalam aturan bisnis itu sendiri merupakan aturan
bisnis yang menggambarkan cara orang berpikir dan berbicara tentang berbagai
hal. Dengan demikian, mendefinisikan istilah adalah menetapkan kategori aturan
bisnis. Secara tradisional, istilah telah didokumentasikan dalam Glosarium atau
sebagai entitas dalam model konseptual.
3. Menetapkan peraturan perusahaan
Sifat atau struktur operasi suatu organisasi dapat ditetapkan dan
dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang berlaku dalam perusahaan.
26
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Dalam menetapkan peraturan perusahaan, termasuk didalamnya terkait proses
pemasaran, manajemen, akuntasi, dan sebagainya, Umumnya, perusahaan yang
berorientasi dalam jangka panjang, telah menetapkan peraturan perusahaan dalam
sebuah prosedur, yang disebut sebagai SOP *Standard of Operasional Procedure”
..
27
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
III. FUNGSI MANAJEMEN DALAM AGRIBISNIS
Usaha pertanian secara modern dengan konsep agribisnis menuntut untuk
menerapkan manajemen dalam setiap kegiatannya sebagaimana kegiatan usaha
lain,; baik pada sektor input, produksi, pasca panen dan pemasaran.
Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan
dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia, melalui kegiatan Planning
(perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan) dan
Controlling (pengawasan/ pengendalian/evaluasi).
Manajemen dibutuhkan oleh semua tipe organisasi dan semua kegiatan
yang diorganisasikan, serta dimana saja orang bekerja bersama untuk mencapai
tujuan. Tanpa manajemen semua usaha akan sulit mencapai tujuan. Ada tiga
alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu:
1) Untuk mencapai tujuan, baik tujuan organisasi maupun pribadi
2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling
bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti
pemilik dan karyawan, kreditur, pelanggan, konsumen, serikat kerja,
masyarakat dan pemerintah.
3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara, satu diantaranya
yang umum digunakan adalah efisiensi dan efektivitas.
Dua hal ini (efisiensi dan efektivitas) merupakan dua konsepsi utama
yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja manajemen.
Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar
(doing things right). Hal ini merupakan konsep maternatik, yang merupakan
28
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
perhitungan ratio antara keluaran (output) dan masukan (input). Semakin besar
ratio maka manajemen semakin efisien. Artinya manajer dapat meminumkan
biaya penggunaaan sumber-sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah
ditentukan atau manajer dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan
yang terbatas.
Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau
peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (doing the
rigth things). Hal yang penting bagi para manajer adalah bagaimana menemukan
pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan bukan bagaimana hanya sekedar
melakukan pekerjaan dengan benar.
Fungsi-fungsi dalam prinsip manajemen berlaku pada agrinsnis,. Namun
tindakan yang lebih dari itu adalah ia harus dapat memimpin, merencanakan,
mengorganisasikan, dan mengontrol tim kerja yang ia pimpin. Seseorang yang
memegang posisi manajemen di dalam organisasi diperlukan untuk berpikir
secara strategis dan konseptual untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam
memimpin, maka fungsi manajemen mencakup empat fungsi manajemen dan
bagaimana fungsi-fungsi ini akan berperan dalam keberhasilan organisasi.
Empat fungsi manajer adalah menjalankan perencanaan, pengorganisasian,
memimpin, dan pengendalian. Dua bagian terakhir - memimpin dan
mengendalikan - merupakan dua kegiatan yang harus dijalankan secara efektif
agar dapat mencapai keberhasilan organisasi. Manajer harus terlebih dahulu
merencanakan, kemudian mengatur sesuai dengan rencana itu, memimpin orang
lain untuk bekerja menuju rencana, dan akhirnya mengevaluasi efektivitas rencana
29
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
tersebut. Keempat fungsi ini harus dilakukan dengan benar dan, ketika dilakukan
dengan baik, maka keberhasilan organisasi akan diraih.
3.1. Perencanaan merupakan fungsi pertama
Fungsi manajerial pertama adalah perencanaan, yang dilakukan dengan
membuat rencana aksi yang terperinci untuk mencapai beberapa tujuan organisasi.
Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran memiliki tujuan meningkatkan
penjualan selama bulan Februari. Ia terlebih dahulu harus menghabiskan waktu
memetakan langkah-langkah penting yang harus diambil oleh tim penjualannya
agar mereka dapat meningkatkan angka penjualan. Langkah-langkah ini dapat
mencakup hal-hal seperti meningkatkan iklan di wilayah tertentu, menempatkan
beberapa barang yang dijual pada lokasi-lokasi penjualan yang strategis,
meningkatkan jumlah kontak perwakilan pelanggan-ke-penjualan yang
diperlukan, atau menghubungi pelanggan sebelumnya untuk melihat apakah
mereka tertarik untuk membeli produk tambahan. Langkah-langkahnya kemudian
diorganisasikan ke dalam pola yang logis sehingga ia dan timnya dapat mengikuti
kemauan konsumen.
Perencanaan adalah penentuan kegiatan-kegiatan sebelum dilaksanakan,
meliputi apa (What), bila (When), dimana (Where), Mengapa (Why), siapa (Who)
dan bagaimana (How) hal itu dailakukan. Dengan demikian perencanaan pada
dasarnya adalah (1) menetapkan tujuan, (2) memilih cara terbaik (strategi,
kebijakan, prosedur, metode, system, anggaran dan standar) untuk mencapai
tujuan tersebut. Dalam hal ini pengambilan keputusan merupakan bagian penting
dalam perencanaan terutama dalam memilih alternative dari beberapa alternative
yang ada dalam pencapaian tujuan dengan mempertimbangka sumberdaya-
30
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.
Dalam mengambil keputusan harus dapat mengantisipasi kejadian-
kejadian di masa mendatang, problem-problem dan hubungan-hubungan
sebab akibat yang mungkin dapat terjadi. Dalam hal ini kemampuan untuk
meramalkan kejadian yang akan datang menjadi persyaratan dalam
menyusun sebuah rencana yang baik. Adanya faktor ketidakpastian yang
dihadapi organisasi di masa mendatang mengharuskan setiap manajer siap
menghadapinya dengan mengembangkan berbagai rencana alternatif.
Jadi perencanaan mencakup proses kegiatan yang melihat ke depan,
mengembangkan tindakan altenatif dan mempelajari hasil -hasil yang
mungkin dicapai dari masing-masing tindakan altenatif dan selanjutnya
dipilih tindakan yang terbaik.
Perencanaan juga merupakan langkah berkelanjutan, dan dapat sangat
khusus berdasarkan sasaran organisasi, sasaran divisi, sasaran departemen, dan
sasaran tim. Seorang manager dapat memutuskan kemana tujuan yang perlu
direncanakan di dalam area / wilayah yang dipimpinnya..
3.3. Fungsi Kedua : Mengatur
Fungsi manajerial kedua adalah mengatur langkah yang dibutuhkan.
Seorang manajer menentukan bagaimana dia akan mendistribusikan sumber daya
manusia dan mengatur karyawannya sesuai dengan rencana. Ia perlu
mengidentifikasi peran yang berbeda dan memastikan bahwa dia menetapkan
jumlah karyawan yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Dia juga perlu
mendelegasikan otoritas, menugaskan pekerjaan, dan memberikan arahan
31
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
sehingga tim perwakilan penjualannya dapat bekerja menuju angka penjualan
yang lebih tinggi tanpa hambatan di tempat penjualan.
Fungsi mengatur atau pengorganisasian adalah proses menetapkan dan
mengelompokkan orang, alat, tugas dan tanggung jawab sedemikian rupa
sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu
kesatuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain
penggerakkan adalah (1) penentuan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) perancangan dan
pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa
hal-hal tersebut ke arah tujuan, (3) penentuan tanggung jawab, dan (4)
pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada bawahan untuk
melaksanakan tugasnya. Semua hal tersebut adalah menciptakan struktur formal
dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan yang sering dikenal
dengan sebutan struktur organisasi. Perbedaan tujuan organisasi akan
menghasilkan struktur yang berbeda pula.
3.3. Fungsi ketiga : Memimpin
Dalam langkah ini, seorang manajer menghabiskan waktu untuk
berhubungan dengan karyawannya pada level interpersonal. Hal ini merupakan
pekerjaan yang tidak sekedar mengelola tugas; melainkan melibatkan
berkomunikasi, memotivasi, menginspirasi, dan mendorong karyawan untuk
menuju tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Tidak semua manajer dapat
menjadi seorang pemimpin, namum ia harus dapat menjadi panutan bagi
karyawannya. Seorang karyawan akan mengikuti arahan dari seorang manajer
karena mereka harus melakukannya, tetapi seorang karyawan akan secara sukarela
32
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
mengikuti arahan dari seorang pemimpin jika pemimpin itu dapat menjadi
panutan bagi dirinya.
Fungsi memimpin juga disebut sebagai menggerakkan, yakni tindakan-
tindakan manajer meliputi memotivasi, memimpin, mempengaruhi bawahan dan
komunikasi untuk membuat para karyawan mau melaksanakan tugas yang telah
ditetapkan dengan sukarela dan kerjasama yang balk. Tindakan ini dianggap
sebagai mengarahkan pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam sebuah
organisasi. Penggerakkan sangat berkaitan erat dengan fungsi-fungsi manajemen
lainnya, seperti perencanaan , pengorganisasian dan pengawasan agar tujuan-tujuan
organisasi dapat dicapai.
Pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak
mencakup aspek abstrak proses manajemen, maka kegiatan penggerakkan
berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Oleh karenanya
dalam menggerakkan orang, dibutuhklan keterampilan pendekatan atau
menggunakan seni pendekatan, melalui cara-cara yang tepat sehingga tujuan
menggerakkan orang lain dapat tercapai.
3. 4. Fungsi Kontrol Manajemen
Pengawasan adalah kegiatan manajer untuk mengusahakan agar
pekerjaan pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan
berusaha menemukan dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Fungsi
pengawasan meliputi empat hal, yaitu :
(1) menetapkan standar prestasi,
(2) mengukur prestasi kerja yang telah dicapai selama ini,
(3) membandingkan prestasi kerja yang telah dicapai dengan standar
33
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
prestasi, dan
(4) melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan telah terjadi
penyimpangan dari standar prestasi yang ditetapkan .
Tindakan dapat berupa memperbaiki peralatan yang rusak, mengubah
perilaku karyawan, mereorganisasi departemen dan merevisi rencana.
Fungsi pengawasan dapat bermakna positif dan negatif Pengawasan positif
artinya pengawasan mencoba mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai
dengan efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan negatif adalah mencoba
menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.
Hubungan diantara fungsi-fungsi manajemen tersebut akan digambarkan seperti
pada gambar berikut.
Perencanaan
Penetapan tujuan dan
strategi, kebijakan,
prosedur dll
Pengawasan Pengorganisasian
Penetapan standar, Penentuan sumber daya
mengukur prestasi, & kegiatan, menyusun
membandingkan prestasi organisasi,
dengan standar dan penentuan tanggung
mengambil tindakan jawab, delegasi
koreksi wewenang
Penggerakkan
Motivasi,
kepemimpinan,
komunikasi untuk
mengarahkan bawahan
Gambar 2. Hubungan Diantara Fungsi-fungsi Manajemen
Sumber : Hindarti, 2019
34
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Fungsi ini dapat menjadi penentu penting keberhasilan organisasi. Fungsi
kontrol tidak berarti hanya mengontrol melalui umpan balik dan melakukan
proses penyesuaian, namun tindakan yang lebih luas dapat berlanjut : Apakah
kontrol yang dilakukan sudah baik? Bagaimana cara mengontrol yang baik?
Kontrol dilakukan setelah strategi ditetapkan dan rencana dibuat,
kemudian kontrol merupakan langkah-langkah untuk memastikan apakah
rencana sudah direalisasikan, atau, jika kondisi mengijinkan, bisa terjadi sebuah
rencana dimodifikasi. Hal ini dilakukan sebagai fungsi kontrol kritis manajemen.
Fungsi ini dilakukan untuk memastikan orang lain melakukan apa yang harus
dilakukan. Banyak literatur manajemen berupa nasihat tentang cara mencapai
kontrol yang lebih baik. Nasihat ini biasanya mencakup uraian tentang beberapa
jenis pengukuran dan proses umpan balik. Adapun dalam proses pengendalian
dasar, melibatkan tiga langkah yang hendaknya dilakukan :
(1) menetapkan standar.
(2) mengukur kinerja terhadap standar yang telah ditetapkan
(3) mengoreksi penyimpangan dari standar dan rencana
Sistem kontrol manajemen yang baik adalah sistem yang dapat
merangsang tindakan dengan menemukan variasi signifikan dari rencana awal dan
berfokus kepada tujuan yang sudah ditetapkan.
Hal yang dibutuhkan adalah perspektif yang lebih luas tentang kontrol
sebagai fungsi manajemen: Perspektif semacam ini merupakan :
(1) bagian pertama yang merangkum masalah kontrol umum dengan
mendiskusikan alasan mendasar mengapa kontrol diterapkan dan dapat
menggambarkan apa yang dapat dicapai secara realistis.
35
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(2) Di bagian kedua, berbagai jenis kontrol yang tersedia diidentifikasi.
(3) Bagian terakhir membahas mengapa pilihan kontrol yang tepat dan
harus berbeda dalam pengaturan yang berbeda.
3.4.1. Mengapa Kontrol Dibutuhkan?
Jika semua karyawan selalu melakukan apa yang terbaik untuk organisasi,
dengan siap dikontrol, maka manajemen bahkan tidak diperlukan. Namun, dalam
kenyataannya, setiap individu kadang-kadang tidak mampu atau tidak mau
bertindak untuk kepentingan terbaik organisasi, dan seperangkat kontrol harus
dilaksanakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan dan untuk
mendorong tindakan yang diinginkan.
Hal yang patut dipahami adalah, bahwa sistem kontrol perlu dilakukan
dalam keadaan “berjaga” akan keterbatasan pribadi. Hampir setiap orang tidak
selalu mengerti apa yang diharapkan dari perusahaan atau organisasi, dengan
melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Namun karena mereka
mungkin kekurangan kemampuan, pelatihan, atau informasi yang diperlukan,
maka tindakan mereka tidak memuaskan organisasi. Selain itu, manusia memiliki
sejumlah bias perseptual dan kognitif bawaan, seperti ketidakmampuan untuk
memproses informasi baru secara optimal atau bagamana membuat keputusan
yang konsisten, dan bias ini dapat mengurangi efektivitas organisasi. Keterbatasan
pribadi dapat diperbaiki atau dihindari, tetapi kontrol selalu diperlukan untuk
menjaga dari pengaruh buruk karyawan.
Bahkan karyawan yang dipastikan sudah dilengkapi dengan pengetahuan baik
untuk melakukan pekerjaan dengan baik, beberapa diantaranya memilih untuk
tidak melakukannya, karena sasaran individu dan tujuan organisasi mungkin tidak
36
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
sesuai dengan sempurna., terutama dengan sasaran dan tujuan masing-masing
individu. Dengan kata lain, perlu dilakukan keselarasan tujuan untuk mencegah
karyawan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri .
Jika keterbatasan pribadi dan masalah motivasi terganggu, maka dampak
yang berat dapat terjadi. Minimal, kontrol yang tidak memadai dapat
menghasilkan kinerja yang lebih rendah atau risiko kinerja yang lebih buruk. Pada
titik ekstrim, jika kinerja tidak dikontrol pada satu atau lebih dimensi kinerja
penting, hasilnya bisa berupa kegagalan organisasi.
3.4.2. Perlunya Kontrol / Pengendalian yang Baik
Kontrol sempurna, dapat menjadi jaminan bahwa pencapaian yang
sebenarnya akan berjalan sesuai rencana, tidak pernah mungkin karena
kemungkinan terjadinya peristiwa yang tak terduga. Namun, kontrol yang baik
seharusnya seseorang yang berpengetahuan bisa cukup yakin bahwa tidak ada
kegagalan terjadi. Kontrol yang baik adalah kontrol yang berorientasi kepada
masa depan: tujuannya agar tidak terjadi kegagalan di masa depan. Masa lalu
tidak relevan dibuat alasan kecuali sebagai panduan untuk masa depan.
Dengan berbekal dapat melaksanakan fungsi-fungsi di atas, maka seorang
manajer pertanian seharusnya mampu merencanakan dan mengoordinasikan
operasi pertanian, pembibitan, rumah kaca, dan lokasi produksi pertanian lainnya.
Dalam pengaturan kerja yang lebih besar manajer juga dapat mempekerjakan dan
melatih petani untuk merawat tanaman di bawah pengawasan manajer.
Manajer pertanian mengawasi semua aspek termasuk menjalankan
peternakan dan fasilitas lain yang menghasilkan tanaman. Beberapa tugas manajer
meliputi perencanaan, pengawasan, dan terkadang berpartisipasi dalam proses
37
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
penanaman, pembuahan, dan panen. Manajer bisa bertanggung jawab untuk
merekrut, melatih, dan mengelola pekerja pertanian, memastikan bahwa orang
yang direkrut benar dapat disiapkan untuk posisi penting dalam operasional
pertanian. Manajer juga terlibat dalam memilih peralatan dan persediaan yang
tepat yang diperlukan untuk mendukung jalannya operasional pertanian.
Tergantung pada ukuran dan fasilitas yang tersedia, manajer pertanian mungkin
juga diminta untuk menyimpan semua data untuk keperluan pembukuan/akuntansi
sekaligus mampu untuk memasarkan hasil pertanian.
Manajer pertanian menghabiskan banyak waktu bekerja di lingkungan
pertanian, yang berarti bahwa sebagian besar hari kerja berlangsung di luar
ruangan. Mereka mungkin banyak terpapar matahari dengan kondisi cuaca yang
kadang-kadang sangat panas hampir setiap hari dan sering melakukan pekerjaan
berat secara fisik. Namun, beberapa waktu mereka mungkin dihabiskan di dalam
ruangan untuk merencanakan apa yang akan ditanam untuk musim berikutnya,
bagaimana pemasaran hasil tanaman mereka, atau memelihara peralatan yang
dibutuhkan untuk menjalankan pertanian secara efisien.
Oleh karenanya, kebanyakan manajer pertanian bekerja penuh waktu
dengan potensi besar untuk lembur. Selama musim kering adalah waktu tersibuk
dalam setahun, yang barangkali para manajer bekerja dari matahari terbit hingga
terbenam. Oleh karenanya, gaji seorang manajer pertanian diharapkan layak
disebut cukup, Di Amerika Serikat, gaji manajer pertanian rata-rata mencapai
$ 69.300 setahun ( Anonymous, 2018) atau sekitar $ 5,557 per bulan yang jumlah
ini cukup besar bagi manajer Indonesia. Sepuluh persen terendah bergaji sekitar $
31.700 per tahun atau $2,642 per bulan, sedangkan 10% tertinggi menghasilkan
38
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
sekitar $ 124.160 per tahun atau $10,347 per bulan (Anonymousa, 2018).
Penghasilan tersebut dapat berfluktuasi tergantung pada hasil pertanian pada
tahun tertentu, serta penerimaan subsidi pemerintah dan manfaat lainnya. Dalam
hal ini, perlu dipahami berapa hasil pertanian yang dicapai dalam satu tahun, dan
berapa yang diterima dari subsidi pertanian dari Pemerintah, serta ada penopang
lainnya seperti bantuan dari perusahaan yang sudah mapan, sebagai CSR
(Corporate Social Responsibility). Di negera maju seperti Amerika Serikat, petani
mempunyai subsidi yang cukup besar dari Pemerintah. Hampir semua biaya
operasional pertanian memperoleh bantuan dari Pemerintah AS (Muhaimin dan
Sari, 2017), sehingga tidak mengherankan jika gaji manajer pertanian cukup
layak. Namun demikian, kebanyakan manajer pertanian di AS memiliki dan
mengoperasikan bisnis mereka sendiri, sedangkan mereka yang bekerja untuk
orang lain, umumnya bekerja untuk perusahaan besar dan karir manajer pertanian
berfokus kepada sumber dan pengadaan strategis, manajemen resiko,
berhubungan dengan pemasok(supplier), dan melakukan integrasi dengan
pemasok sebagai elemen utama pekerjaan yang terkait. Meskipun pekerjaan
manajer pertanian bervariasi, sebagian besar mereka merasa nyaman dengan
melakukan tugas berikut dalam lingkup profesinya (Anonymous, 2018).
3.4.3. Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Pertanian
Lebih lanjut, uraian pekerjaan (job desription) seorang manajer pertanian
adalah sebagai berikut (Anonymousa, 2018):
(1) Menggunakan sumber strategis untuk mengembangkan dan mendorong
strategi dan proses pelaksanaan strategi itu untuk kemajuan perusahaan.
39
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(2) Mengembangkan dan memimpin kegiatan sumber strategis, termasuk analisis
internal dan eksternal dan negosiasi
(3) Melacak perubahan pasar ke depan berdasarkan perubahan lingkungan pasar
(4) Mengembangkan dan mempromosikan keragaman pemasok yang kuat
(5) Mempersiapkan proyeksi komoditas bulanan
(6) Melacak total biaya kepemilikan dan variasi anggaran
(7) Mempunyai pengetahuan tentang pengadaan dan manajemen rantai pasok
karena terkait dengan industri pertanian
(8) Menguasai pengetahuan umum terutama tentang
produksi, pasar, dan proses rantai pasokan komoditas pertanian
(9) Mampu memimpin kegiatan bisnis yang sedang berlangsung
(10) Mempunyai kinerja yang terukur dengan KPI (Key Performance Indicator)
yang sudah umum diterapkan oleh sebagian besar organisasi dalam memantau dan
melacak kinerja seseorang (Schrage, 2018). Para konsultan Sumber Daya
Manusia menetapkan transparansi KPI yang lebih besar pada bagian yang paling
penting, seperti pemasaran, penjualan, keuangan, dan proses dalam manajemen
organisasi dan beberapa perusahaan besar menerapkannya, seperti Adidas,
Colgate-Palmolive, dan GoDaddy, meski ada pula perusahaan lain seperti GE
Healthcare menggunakan KPI untuk meningkatkan efektivitas bekerja (Schrage,
2018). Menurut Scharge (2018), perusahaan berbasis data yang canggih tidak
hanya menggunakan KPI, tetapi juga mengharapkan manajer untuk lebih
berperan kepada fungsi mengatur. Indikator lain yang digunakan selain KPI
adalah RAROC (risk-adjusted return of capital) dan NPS (Net Promoter Score)
40
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
yang mengukur bagaimana kepemimpinan secara eksplisit memegang dirinya
sendiri untuk bertanggung jawab.
KPI mengukur produktivitas dan keterlibatan orang, tim, dan bakat
organisasi. KPI dapat berfokus kepada manajer yang paling memotivasi secara
efektif, misalnya, atau manajer melemahkan semangat kerja. KPI juga dapat
menunjukkan tingkat inisiatif dan inovasi produktivitas.
(11) Mengelola dan mengkoordinasikan semua fase produksi pertanian mulai dari
penanaman hingga panen.
(12) Maksimalkan hasil premium dengan biaya yang paling efektif
(13) Bersedia untuk mendekati pertanian secara holistik tetapi dengan pola pikir
bisnis.
(14) Memiliki lingkup pengetahuan yang luas yang mencakup ilmu tanaman dan
tanah, meteorologi, fisiologi tanaman, dan bidang terkait seperti penerapan
statistika dalam membuat model peramalan.
(15) Mengkomunikasikan temuan kepada rekan kerja, petani, dan masyarakat.
Lima belas poin di atas merupakan tugas seorang manager pertanian yang
seharusnya dapat ditangani. Pekerjaan manajer pertanian senior sering memiliki
lingkup yang lebih luas yang mungkin termasuk pengelolaan semua aset pertanian
serta operasi dan personalia. . Tanggung jawab seperti itu mungkin termasuk:
(16) Menegakkan peraturan pemerintah
(17) Mampu membuat/menulis proposal hibah dan bisnis untuk tujuan pendanaan
(18) Memimpin / mengkoordinasikan upaya lintas fungsional untuk mendukung
kegiatan terkait kualitas bahan, inovasi produk, dan tanggung jawab sosial
perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSR)
41
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(19) Memimpin kelompok lintas fungsional untuk mengembangkan program
produktivitas yang memberikan target yang mungkin tercapai dan melaksanakan
Total Procurement Value (TPV). TPV adalah nilai pencapaian dalam pengadaan
barang yang paling efisien.
(20) . Mengembangkan dan mengartikulasikan strategi komoditas bulanan untuk
CPO (Chief Procurement Oddicer – para staff bagian pengadaan) dan melakukan
kepemimpinan pengadaan serta laporan lain sesuai kebutuhan
(21) Mengembangkan informasi spesifik kategori tentang pembelanjaan, kinerja
pemasok, kepatuhan, standar dan spesifikasi, serta tolak ukur industry
(22) Mengelola semua personil termasuk penggajian, perekrutan, pemberhentian,
PHK, penjadwalan, pelatihan, dan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk
memenuhi tanggung jawab pekerjaan.
(23) Mengawasi semua aspek produksi, termasuk namun tidak terbatas pada
pemupukan, pemangkasan, irigasi, penyemprotan, pemeliharaan tanah, panen,
pengepakan, penyimpanan, dan logistic
(24) Mengembangkan dan mengelola anggaran tahunan
(25) Menggunakan konsultan untuk meneliti dan menerapkan teknologi pertanian
/ hortikultura baru
(26) Menerapkan standar pertumbuhan dan kualitas
(27) Menerapkan dan mengelola kebijakan dan praktik keamanan manusia dan
makanan untuk semua karyawan dan pihak ketiga
(28) Meninjau penelitian yang sedang dilakukansehubungan pengajuan untuk
mengembangkan pengetahuan hortikultura dan teknis pelaksanaannya
(29) Terlibat dalam persiapan laporan teknis
42
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(30) Menumbuhkan lingkungan kerja yang positif dan aman dengan memberi
kesempatan memberikan bimbingan
(31) Menavigasi peraturan regional, federal dan internasional, dan
melaksanakannya dengan praktik terbaik
(32) Berhubungan dengan para pemangku kepentingan dan mitra pertanian
(33) Berkonsultasi dengan petani, insinyur(ahli pertanian), rekan ilmuwan, dan
lembaga pemerintah terkait memperoleh praktik terbaik
Demikian harapan dan permintaan dari seorang manajer pertanian yang
berlaku di Amerika Serikat yang tidak menutup kemungkinan tugas dan tanggung
jawab yang sama berlaku di Indonesia.
Menurut Anonymousa (2018), permintaan pekerjaan untuk Manajer
Pertanian di AS diperkirakan menurun sebesar 19% dalam sepuluh tahun ke
depan. Penurunan ini dapat disebabkan karena terjadinya industrialisasi pertanian,
yang membutuhkan lebih sedikit manajer dan pekerja untuk menghasilkan hasil
yang lebih besar. Harga untuk pasokan/input pertanian juga telah meningkat
tajam dalam beberapa tahun terakhir, membuat perusahaan swasta jauh lebih sulit
untuk beroperasi. Namun, pemerintah AS dan berbagai organisasi nirlaba
menyediakan banyak opsi untuk fasilitas pertanian milik pribadi. Banyak
perusahaan juga dapat menemukan ceruk pasar yang lebih memilih makanan
kecil, gaya makanan yang cepat saji di atas meja. Meskipun jumlah pekerjaan
menurun, masih ada harapan untuk jalur karir seorang manajer pertanian ,
terutama yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang diperlukan, meskipun
banyak memiliki setidaknya ijazah sekolah menengah kejuruan (SMK).
Kebanyakan manajer pertanian mendapatkan pelatihan melalui pengalaman kerja,
43
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
magang di perusahaan pertanian lokal, atau mewarisi pertanian keluarga. Namun,
penting untuk dicatat bahwa gelar sarjana secara perlahan muncul sebagai aset
penting dalam industri. Oleh karenanya, mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
dan mendapatkan gelar dalam bidang pertanian, manajemen pertanian, agronomi,
atau botani dapat memberikan informasi penting tentang tanaman, kondisi cuaca
yang ideal, dan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan tanaman tidak
bertumbuh baik, dan hal itu akan sangat mendukung pekerjaan sebagai seorang
manajer pertanian.
44
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
IV. KEKHUSUSAN MANAJEMEN AGRIBISNIS
Jika secara fungsional (penerapan fungsi-fungsi manajemen) dalam
agribisnis tidak berbeda dengan manajemen pada usaha lain (non agribisnis),
tetapi mengingat bahwa produk pertanian memiliki kekhususan dalam berbagai
hal maka manajemennya berbeda dengan usaha lain (Downey and
Erickson,1987). Kekhususan manajemen agribisnis diantaranya disebabkan :
1) Keanekaragaman jenis bisnis yang luas
2) Besarnya jumlah usaha pertanian Agribisnis yang dapat dijangkau
3) Kanekaragaman ukuran usaha
4) Agribisnis skala kecil harus bersaing dengan yang skala besar
5) Falsafah hidup tradisional
6) Cenderung berorientasi pada keluarga dan masyarakat
7) Sifat produk musiman
8) Bertalian dengan gejala alam
9) Produk tidak tahan lama
10) Produk mudah rusak
11) Dampak program & kebijakan pemerintah mengena langsung pada pelaku-
pelaku Agribisnis
4.1. Banyaknya Faktor yang Berpengaruh dalam Agribisnis
Selain sifat /karakteristik produk pertanian yang beragam, juga terdapat
faktor-faktor yang mempengaruhi pasokan produk pertanian, sbb ( Tong, 2018):
1. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga produk pertanian
45
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
terutama adanya ketegangan hubungan permintaan dan penawaran, biaya
produksi, biaya sirkulasi dan spekulasi dari pemilik modal dadakan (Hot
Money).
2. Faktor-faktor yang menyebabkan harga rendah dan penjualan produk
pertanian yang sulit terutama mencakup asimetri informasi penawaran-
permintaan, kurangnya alat manajemen risiko untuk harga produk
pertanian dan operasi petani skala kecil yang terdesentralisasi.
Atas dasar faktor-faktor inilah, maka Tong (2018) menyajikan
langkah-langkah penanggulangan berikut saran untuk menstabilkan harga
produk pertanian:
Pertama, membangun mekanisme yang tepat untuk produksi dan penjualan
produk pertanian;
Kedua, memperluas produksi dan meningkatkan pasokan produk pertanian;
Ketiga, mengendalikan kisaran kenaikan biaya produksi untuk produk pertanian;
Kempat, tingkatkan tingkat organisasi petani;
Kelima, mempromosikan inovasi dan pengembangan alat manajemen risiko
untuk harga produk pertanian.
Dengan berkembangnya jaman, permintaan terhadap produk pertanian
tradisional memang cenderung ,menurun, terlebih jika tanpa dibarengi
penambahan nilai (value-added) dari produk tersebut, namun peran agribisnis
meningkat jika produk tersebut dikelola dengan profesional, bahkan hasilnya
cukup menggembirakan, Artinya, peran agribisnis meningkat terutama dalam
ekonomi pertanian, yang tidak saja di Indonesia, namun juga di negara-negara lain
(Heiman et all, 2002 )
46
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Meningkatnya peran agribisnis tersebut disebabkan karena meningkatnya
kebutuhan akan ekonomi dan manajemen sektor pangan serta lingkungan hidup,
terlebih Departemen Ekonomi Pertanian di Amerika Serikat, telah menunjukkan
fleksibilitas yang besar terhadap pengajaran agribisnis dalam program pengajaran
Sarjana hingga jenjang pHd mereka. Program-program penelitian agribisnis
berkembang sedemikan rupa, menyesuaikan adanya permintaan, meski berjalan
sedikit lebih lambat sehubungan perubahan permintaan. Program ekonomi
pertanian selanjutnya memmbuka peluang untuk program bersama dengan ilmu
biologi, fisik, dan alam, khususnya manajemen sumber daya alam yang
diupayakan tidak dieksploitasi seperti masa lalu. .Profesi agribisnis di masa depan
diharapkan tetap hidup dalam jangka panjang, meski harus terus berkembang,
mengembangkan berbagai peluang dalam agribisnis dengan disiplin biologis,
fisik, dan alam, untuk memenuhi tuntutan dari pasar yang berubah.
Konsep agribisnis yang dibahas adalah agribisnis yang tidak hanya
mencakup pengelolaan lahan yang produktif saja, tetapi juga orang-orang yang
bekerja didalamnya, termasuk perusahaan-perusahaan yang terlibat didalamnya.
Adapun produk yang terkait , mulai dari input (yaitu benih, pupuk, kredit,
dll.), hingga ke proses output ( susu, biji-bijian, daging dll.), memproduksi produk
makanan (misalnya es krim, roti, sereal sarapan, dll.), dan menjalankan
transportasi hingga menjual produk makanan ke konsumen. Fokus dalam
agribisnis kemudian mengarah kepada pemenuhan kebutuhan input yang
digunakan dalam produksi pertanian seperti benih, pagar, mesin dan seterusnya,
hingga perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri yang membentuk
“sektor input pertanian”. Dengan demikian, input pertanian digolongkan ke
47
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
dalam bagian pertama agribisnis dan menghasilkan berbagai produk berbasis
teknologi, yang besarnya sekitar 75 persen dari semua input yang digunakan
dalam produksi pertanian. Pada saat yang sama, sektor input pertanian
berkembang, evaluasi serupa juga berlangsung pada pengolahan komoditas dan
manufaktur makanan, yang kemudian diikuti dengan berkembangnya bidang
peternakan karena mengkonsuimsi hasil pertanian seperti hasil pakan ternak.
Bentuk hasil pertanian yang berubah seperti gandum, beras, susu, ternak dan
sebagainya) masih berubah lebih lanjut agar lebih bermanfaat untuk konsumsi
masyarakat, seperti pembuatan kue, camilan dan sebagainya; dengan
mengolahnya menjadi
komoditas olahan (tepung) bukan komoditas pertanian mentah (gandum).
Selama periode tersebut, kemajuan teknologi terus bekembang agar
dapat dibuat proses lebih lanjut, seperti pengawetan makanan. Seperti diketahui,
produk pertanian mempunyai sifat mudah rusak dan kadangkala hanya tersedia
pada saat panen saja. Oleh karenanya, makanan perlu diawetkan agar
memungkinkan untuk tersedia kapan saja sepanjang tahun. Kini, banyak petani
turut mengkonsumsi produk yang sudah diproses dibandingkan dengan
mengolahnya sendiri.
Hasil peternakan yang bertemu dengan kebutuhan dan permintaan
konsumen kemudian digolongkan kepada bagian agribisnis sebagai sektor
manufaktur pengolahan.
4.2 Pentingnya Pengetahuan Dalam Agribisnis
Dunia pertanian cukup dekat dengan kehidupan manusia, terlebih di
Indonesia yang beriklim tropis. Demikian pula dengan negara-negara lain di
48
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
sekitarnya yang mengangap pertanian sebagai tulang punggung perekonomian.
Di negara-negara dengan basis pertanian, pastinya hasil pertanian menyumbang
dalam jumlah signifikan kepada Produk Domestik Bruto (PDB) negara,
menyediakan lapangan kerja dengan jumlah yang cukup besar dan mampu
memenuhi kebutuhan pangan dan gizi warga bangsa. Bagi Indonesia pun, hasil
pertanian mampu menyediakan bahan baku penting untuk beberapa industri besar,
seperti kelapa sawit, karet, cokelat dan lain-lain. Dunia pertanian masa kini
menghadapi banyak tantangan dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan
cepat, laju globalisasi teknologi, lingkungan yang kompetitif dan adanya peran
perubahan di sektor politik. Oleh karenanya, sektor pertanian kini telah
merambah perdagangan komersial dan mampu mengubah dunia pertanian yang
semula subsisten, menuju kepada pertanian komersial dengan meningkatnya
ekspor produk pertanian, dan bahkan impor yang tidak kunjung berhenti. Adanya
perubahan teknologi, tidak mampu membendung arus impor karena Indonesia
mengalami pasokan barang pertanian yang kurang cukup menutupi permintaan
masyarakat. Gula, beras, cabe, bawang, dan produk-produk lainnya terdesak untuk
diimpor memenuhi permintaan yang terus bergerak naik. Perkembangan teknologi
tidak mampu mengalahkan permintaan yang terus meningkat, yang menunjukkan
bahwa laju percepatan hasil pertanian tidak mampu berimbang dengan naiknya
permintaan. Oleh karenanya, peran manajemen yang baik dan benar sudah harus
diterapkan untuk menghadapi pasar yang terus berkembang, Contoh yang paling
sering terlihat adalah pasar untuk produk makanan yang diproses dan dikemas,
semakin hari semakin meningkat, yang menunjukkan diperlukannya tenaga yang
terlatih yang mengetahui konsep agribisnis yang mampu dijalankan dengan peran
49
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
manajemen didalamnya. Ajmal (2010) menguraikan, bahwa di Pakistan, hanya 9
persen dari total produk makanan, diproses segar dan 2 persen berperan sebagai
penambahan nilai (value – added), sedangkan 40 persen bahkan terbuang selama
pengemasan dan transportasi. Di Indonesia pun, meski penelitian belum ada
sedetil itu, menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Hal ini
menunjukkan, bahwa pendidikan manajemen agribisnis merupakan suatu
kualifikasi yang mampu membentuk personel menjadi manajer yang baik yang
memiliki keahlian manajerial.
Dalam dunia pertanian, kiprah agribisnis berperan besar dalam mengambil
produk dari petani, yang barangkali pula dijual kembali kepada petani dalam
bentuk yang berbeda. Transaksi yang dilakukan dapat melibatkan produk, atau
layanan dan mencakup hal-hal seperti :
(a) sumber daya produktif misalnya pakan, bibit, peralatan pupuk, energi,
mesin, dll.
(b) komoditas pertanian misalnya makanan dan serat dll.
(c) layanan fasilitatif mis. kredit, pemasaran asuransi, penyimpanan,
pemrosesan, transportasi, pengepakan, distribusi, dll.
Proses – proses yang dijalankan di atas, tentu tidak dapat berjalan baik
tanpa manajemen yang baik pula. Sebab proses-proses tersebut dijalani dengan
langkah-langkah berproduksi, pengolahan, pemasaran dan perdagangan, distribusi
makanan segar dan makanan olahan , pakan, serat termasuk pasokan input dan
layanan untuk kegiatan ini, sehingga mustahil proses-proses tersebut dijalankan
tanpa adanya manajemen didalamnya.
50
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Adapun sistem agribisnis mempunyai keterkaitan yang erat dengan
bagian-bagian yang berperan didalamnya, seperti input pertanian, produksi
pertanian, pengolahan-manufaktur pertanian atau pengolahan pertanian, dan
sektor distribusi-pemasaran pertanian. Keempat sektor ini bertindak sebagai
bagian-bagian yang saling berkaitan dari suatu sistem yang keberhasilan masing-
masing sektor tersebut bergantung sektor-sektor lainnya. Tanpa dilengkapi dengan
manajemen yang tepat, tentu agribisnis sulit mencapai kesuksesan, yang
ditunjukkannya adanya kesuksesan di sektor pangan dan pertanian terkait.
Oleh karenanya, peran manajemen sangat penting, yang tidak lain
merupakan penerapan prinsip manajemen untuk pertanian.
4.3. Menentukan Produk Pertanian yang dipilih
Ruang lingkup agribisnis sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan
pertanian tanaman pangan, namun juga produk peternakan dan tanaman
indubukan makanan, bahkan gabungan antara keduanya. Hal yang penting
diperhatikan adalah, dapat menentukan produk yang dipilih dan memahami
sistem agribisnis tersebut.
Sebagai contoh, produk pertanian organik. Sebelum tanam dimulai, petani
harus membuat keputusan penting yang sangat mempengaruhi manajemen
operasional berikutnya. Pertama dia harus memilih tanaman; persyaratan
operasional yang harus diikuti sesuai tanaman yang sudah dipilihnya, seperti :
(1) Pengelolaan air dalam kaitannya dengan kebutuhan kelembaban tanaman
tersebut
51
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(2) Pengolahan tanah dan persiapan lahan sesuai tanaman yang dipilih,
misalnya ketentuan pH sehingga perlu dilakukan pengapuran (pemberian kapur
agar pH naik) atau mengontrol keasaman.tanah.
(3) Penggunaan pupuk sesuai petunjuk untuk tanaman yang dipilihnya
(4) Perlindungan tanaman demikian pula
Selain itu, petani perlu mengetahui kondisi yang dibutuhkan, seperti iklim,
sifat tanaman dan kebijakan pemanfaatan lahan juga perlu diperhatikan. Faktor-
faktor sosial ekonomi seperti kualitas pengelolaan pertanian, penanaman modal,
penguasaan lahan dan pengaturan pengelolaan air dalam drainase, dsb. Banyaknya
praktik manajemen standar yang digunakan pada tanah mineral ternyata juga
berlaku untuk tanah organik sehingga tidak dibahas secara rinci.
4.4. Menerima Syarat-syarat dan Ketentuan yang Berlaku
Syarat-syarat dan ketentuan yang harus dijalankan dalam menjalankan
sebuah usaha pertanian, telah diatur sama di seluruh dunia, sebagai contoh:
pertanian organik. Bagi usaha yang sudah menjalankan aturan tersebutt, masih
harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat yang menjamin bahwa praktek
yang dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kepemilikan
sertifikat semacam ini menjadikan usaha tersebut memperoleh ‘akreditasi” yang
sesuai dengan yang kelak diiklannya.
Sertifikasi berasal dari kata sertifikat yang berati jaminan tertulis yang
diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan
bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang
dipersyaratkan (Widotono, 2010). . Adapun penerbitan sertifikasi organik
merupakan jaminan dari pihak penerbit sertifikasi atas serangkaian kegiatan
52
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
pertanian organik yang telah memenuhi standar yang dipersyaratkan tentang
Sistem Pangan Organik.
Adapun cara memperolehnya, dengan
mengajukan permohonan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi yang telah
diakreditasi atau diregister/ditunjuk oleh otoritas pemerintah yang berwenang
dalam hal ini Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO).Demikian juga syarat
untu memperoleh HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) atau
Analisis Bahaya Titik Kontrol Kritis, dll. HACCP adalah sistem manajemen di
mana keamanan pangan ditangani melalui analisis dan dilakukan pengendalian
bahaya biologis, kimia, dan fisik dari produksi bahan mentah, pengadaan dan
penanganan, hingga manufaktur, distribusi dan konsumsi produk jadi ( FDA,
2018). HACCP telah lama diterapkan oleh negara-negara maju, seperti Amerika
Serikat dan Uni Eropa. Penerapan HACCP ini cukup krusial dibutuhkan karena
banyaknya produk makanan (tentu kebanyakan dari produk pertanian) yang
mengandung bahaya jika tidak diperlakukan dengan hati-hati. HACCP
mengutamakan kontrol terhadap bahaya yang mungkin timbul dari produk
makanan dan peraturan ini mempunyai panduan serta dilindungi oleh Undang-
Undang Modernisasi Keamanan Pangan FDA, terutama produk makanan yang
dijual di toko ritel, pemroses seafood, ikan, dsb.
FDA mengadakan evaluasi FDA terhadap Program HACCP Seafood
2004/2005 dan saat ini telah mengeluarkan panduan untuk Industri: Seafood
HACCP(FDA, 2018).
Sertifikasi Organik diterbitkan oleh perusahaan konsultan yang sudah
ditunjuk Pemerintah dan pada beberapa kasus bisnis, dibutuhkannya kepemilikan
53
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Sertifikasi Organik agar produk – produk organik yang dihasilkannya, memang
telah benar-benar menjalankan aturan-aturan yang dibutuhkan dalam
menumbuhkan pertanian organik. Fungsi kepemilikan sertifikasi ini juga
merupakan jaminan bahwa tanaman yang dihasilkan benar-benar organik, yang
dibuktikan dengan adanya kepemilikan sertifikasi organik. Perlakukan tanaman
dengan ketentuan syarat dan kondisi yang ditetapkan, menjadi harga tanaman
organik di atas rata-rata tanaman bukan organik. Fungsi dari sertifikasi organik ini
adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui mekanisme sertifikasi
oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).
4.5. Syarat Pertanian Organik
Lembaga Sertifikasi Organik menerbitkan sertifikat bahwa hasil pertanian
itu benar-benar terbebas dari residu kimia. Dengan mendaftarkan atau mengurus
sertifikasi organik pada lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk (dengan
kepemilikan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), maka para LSO
dapat menerbitkan Sertifikasi Organik.
Pertanian organik di definisikan sebagai” sistem produksi pertanian yang
holistik dan rerpadu, dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas
agro-ekosistem secara alami, sehingga menghasilkan pangan dan serat yang
cukup, berkualitas, dan berkelanjutan” IFOAL dalam Husaini dkk (2005). Lebih
lanjut IFOAM (International Federation of Organik Agriculture Movements)
menjelaskan bahwa pertanian organik adalah sistem pertanian yang holistik yang
mendukung dan mempercepat biodiversiti, siklus biologi dan aktivitas biologi
tanah. Serifikasi produk organik yang dihasilkan, penyimpanan, pengolahan,
pasca panen dan pemasaran harus sesuai standar yang ditetapkan oleh badan
54
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
standardisasi. Dalam hal ini penggunaan GMOs (Genetically Modified Organism)
tidak diperbolehkan dalam setiap tahapan pertanian organik mulai produksi
hingga pasca panen.
Adapun Kurniawan (2018) menguraikan pertanian organik adalah sebagai
berikut :
Pertanian Organik adalah sistem produksi pertanian yang tidak
menggunakan pupuk kimia (pabrik), pestisida kimia, herbisida kimia, zat pengatur
tumbuh kimia dan aditif pakan kimia, namun semua penggunaannya adalah
produk organik. Maksud dari pertanian organik adalah budidaya tanaman
berwawasan lingkungan, yakni suatu budidaya pertanian yang direncanakan dan
dilaksanakan dengan memperhatikan sifat-sifat, kondisi dan kelestarian
lingkungan hidup, dengan demikian sumber daya alam dalam lingkungan hidup
dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga kerusakan dan kemunduran
lingkungan dapat dihindarkan dan melestarikan sumber daya agar sumber daya
alam dan lingkungan hidup dapat dilestarikan.
Untuk menghasilkan pertanian organik yang sesuai dengan standar, maka harus
memenuhi beberapa persyaratan tertentu seperti di bawah ini :
1. Penggunaan benih lokal atau benih hibrida yang telah beradaptasi dengan
alam sekitar agar tahan dengan iklim lokal dan bukan benih dari hasil
rekayasa genetika.
2. Menghindari penggunaan pupuk buatan (anorganik) dan pestisida sintesis
sehingga menekan pencemaran udara, tanah dan air.
3. Mempromosikan penggunaan tanah, air, dan udara secara sehat.
55
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
4. Meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari praktik-praktik
pertanian.
5. Kesuburan dan aktivitas biologis tanah pada pertanian organik harus
dijaga dan ditingkatkan dengan menanam tanaman leguminoceae (kacang-
kacangan) atau menanam tanaman yang mempunyai perakaran dalam
melalui program rotasi tanaman yang sesuai.
6. Pengendalian hama, penyakit dan gulma tidak memperkenankan
dengan menggunakan pestisida sintetis. Pengendalian dapat dilakukan
dengan cara pengendalian mekanis, penggunaan pestisida nabati,
penggunaan musuh alami, varietas tahan, rotasi tanaman dan prinsip lain
yang selaras dengan alam.
Jika ketentuan-ketentuan di atas dapat dilaksanakan, maka pertanian
organik dapat dibudidayakan dengan sertifikasi.
Menurut Husain dkk (2005), berdasarkan survey ke lahan petani di Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dilakukan Balai Penelitian Tanah,
berbeda pemahaman tentang pertanian organik di
beberapa petani tergantung pengarahan yang sampai ke petani. Syarat-syarat
pertanian organik diurasikan oleh Husaini dkk (2005) sebagai berikut :
1. Lahan
Lahan yang dapat dijadikan lahan pertanian organik adalah lahan yang
bebas cemaran bahan agrokimia dari pupuk dan pestisida.
Terdapat dua pilihan lahan:
(1) lahan pertanian yang baru dibuka, atau
56
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(2) lahan pertanian intensif yang dikonversi untuk lahan pertanian organik. Lama
masa konversi tergantung sejarah penggunaan lahan, pupuk, pestisida dan jenis
tanaman. Berdasarkan kesesuaian lahan di Indonesia hanya 10 % yang layak
dijadikan lahan pertanian. Mengingat lahan yang bisa diandalkan mendukung
pertanian organik adalah lahan yang tergolong subur dan juga mempertimbangkan
sumber air dan potensial
cemaran dari lahan non organik disekitarnya.
2. Menghindari benih/bibit hasil rekayasa genetika. Sebaiknya benih berasal dari
kebun pertanian organik,
3. Menghindari penggunaan pupuk kimia sintetis, zat pengatur tumbuh, pestisida
kimia
4. Pengendalian hama dilakukan dengan cara mekanis, biologis dan rotasi
tanaman
5 Peningkatan kesuburan tanah dilakukan secara alami melalui penambahan
pupuk organik, sisa tanaman, pupuk alam, dan rotasi dengan tanaman legum.
6. Penanganan pasca panen dan pengawetan bahan pangan menggunakan cara-
cara yang alami.
7. Menangani permasalahan Seputar Pertanian Organik sebagai berikut :
a. Penyediaan pupuk organik
. Pertanian organik mutlak memerlukan pupuk organik sebagai sumber hara
utama. Dalam sistem pertanian organik, ketersediaan hara bagi tanaman harus
berasal dari pupuk organik. Padahal dalam pupuk organik tersebut kandungan
hara per satuan berat kering bahan jauh dibawah kandungan hara yang dihasilkan
oleh pupuk anorganik, seperti Urea, TSP dan KCl. Oleh karenanya, untuk
57
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
memenuhi kebutuhan dasar tanaman (minimum crop requirement) harus
diupayakan semaksimal mungkin.. Sebagai ilustrasi, untuk menanam sayuran
dalam satu bedengan seluas 1 x 10 m saja dibutuhkan pupuk organik (kompos)
sekitar 25 kg untuk 2 kali musim tanam atau setara dengan 25 ton/ha. Bandingkan
dengan penggunaan pupuk anorganik Urea TSP dan KCl yg hanya membutuhkan
total pemupukan sekitar 200-300 kg/ha. Dengan demikian, sumber hara lainnya
lainnya harus dipikirkan, seperti penggunaan pupuk cair secara rutin.
b. Teknologi budidaya pertanian organik .
Teknik bercocok tanam yang benar seperti pemilihan rotasi tanaman
dengan mempertimbangkan efek allelopati dan pemutusan siklus hidup hama
perlu diketahui. Alelopati didefinisikan sebagai suatu fenomena alam bahwa
suatu organisme atau tanaman dapat memproduksi dan mengeluarkan suatu
senyawa biomolekul (disebut alelokimia) ke dalam lingkungan dan senyawa
tersebut memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan organisme lain di
sekitarnya. Sebagian alelopati terjadi pada tumbuhan dan dapat mengakibatkan
tumbuhan di sekitar penghasil alelopati tidak dapat tumbuh atau mati, contoh
tanaman alelopati adalah Eukaliptus (Eucalyptus spp.). Hal ini dilakukan dengan
memenangkan kompetisi nutrisi dengan tanaman lain yang berbeda jenis/spesies.
Oleh karen itu, alelopati dapat diaplikasikan sebagai pembasmi gulma sehingga
mengurangi penggunaan herbisida sintetik yang berbahaya bagi lingkungan.
Pengetahuan akan tanaman yang dapat menyumbangkan hara tanaman
seperti legum sebagai tanaman penyumbang Nitrogen dan unsur hara lainnya
sangatlah membantu untuk kelestarian lahan pertanian organik. Selain itu
58
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
teknologi pencegahan hama dan penyakit juga sangat diperlukan, terutama pada
pembudidayaan pertanian organik di musim hujan.
c. Pemasaran
Pemasaran produk organik di dalam negeri sampai saat ini masih
mempunyai banyak kendala, terlebih harga yang lebih mahal dibandingkan
produk yang bukan organik. Sedangkan untuk pemasaran keluar negeri, produk
organik Indonesia masih sulit menembus pasar internasional meskipun sudah ada
beberapa pengusaha yang pernah menembus pasar international tersebut. Kendala
utama adalah sertifikasi produk oleh suatu badan sertifikasi yang sesuai standar
suatu negara yang akan dituju. Akibat keterbatasan sarana dan prasarana terutama
terkait dengan standar mutu produk, sebagian besar produk pertanian organik
tersebut berbalik memenuhi pasar dalam negeri yang masih memiliki pangsa pasar
cukup luas. Namun banyak terjadi adalah, masing-masing melabel produknya
sebagai produk organik, namun kenyatannya banyak yang masih mencampur
pupuk organik dengan pupuk kimia serta menggunakan sedikit pestisida. Petani
yang benar-benar melaksanakan pertanian organik tentu saja akan merugi alam
hal ini.
d. Kesalahan Persepsi
Masyarakat awam menganggap produk organik adalah produk yang bagus
tidak hanya dari segi kandungan nutrisi namun juga penampilan produknya.
Kenyataannya produk organik itu tidaklah selalu bagus, sebagai contoh daun
berlobang dan berukuran kecil, karena tidak menggunakan pestisida dan zat
perangsang tumbuh atau pupuk an organik lainnya. Penggunaan pupuk organik
tidak memberikan perubahan yang cepat seperti pupuk kimia. Seperti misalnya
59
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
pemupukan Urea akan menghasilkan tanaman yang pertumbuhannya cepat,
sementara dengan pemupukan organik pengaruh perubahan pertumbuhan tanaman
tergolong lambat. Baru pada musim ketiga dan seterusnya, efek pupuk organik
tersebut menunjukkan hasil yang nyata perbedaannya dengan pertanian non
organik. Sehingga dapat disimpulkan pertanian organik di tahun-tahun awal akan
mengalami banyak kendala dan membutuhkan modal yang cukup untuk bertahan.
e. Sertifikasi dan Standarisasi
Beberapa lembaga standarisasi pertanian organik adalah sebagai berikut:
1. Standar Internasional
Standar internasional IFOAM.merupakan standar dasar untuk produk organik
dan prosesnya sejak 1980. Selain itu terdapat The Codex Alimentarius yang
merupakan standar yang disusun dengan penyesuaian standar IFOAM dengan
beberapa standar dan aturan lain.
2. Standard setiap negara : Indonesia melalui Departemen Pertanian juga telah
menyusun standar pertanian organik, tertuang dalam SNI 01-6729-2002. Sistim
pertanian organik menganut paham proses organik, artinya semua proses sistim
pertanian organik dimulai dari penyiapan lahan hingga pasca panen memenuhi
standar budidaya organik,
Gambar di bawah ini merupakan logo organik yang tercantum pada
Sertiikasi Organik :
60
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Gambar 1. . Logo Sertifikasi Organik
Sumber : Triyanto(2016).
Adapun LSO yang terdaftar adalah sbb (Triyanto, 2016) :
1. Sucofindo. dengan No. Sertifikat : OKPO LS-001
Graha Sucofindo Lt.6, Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34, Jakarta 12780, Telp.
(021)7986875, email : customer.service@sucofindo.co.id.
Sucofindo Kantor cabang Surabaya :
Jalan Kalibutuh No. 215, Surabaya 60173. Telp. (031) 5469123
Email: surabaya@sucofindo,co,id.
Sucofindo Kantor Cabang Gresik:
Jalan Wahid Sudiro Husodo No. 154, Gresik 61221. Telp. (031) 3975603
Email : gresik@sucofindo.co.id
Sucofindo Laboratorium Surabaya Lab
Jalan A. Yani no. 315, Surabaya 60260. Telp. 031 847054749.
Email : labsurabaya@sucofindo.co.id
Ruang lingkup :
- Produk segar (tanaman dan produk tanaman pangan, hortikultura,
:palawija dan perkebunan, ternak, ternak : susu, telur, daging dan madu
2. Lembaga Sertifikasi Organik Mutu Agung Lestari (MAL), No sertifikat :
OKPO LS-002.
Alamat : Jalan Raya Bogor No.19, Km 33,5, Cimanggis, Depok.
Telp. (021) 874020 dan 8740202
Email : webmaster@mutucertification.com
Ruang Lingkup :
- Produk segar Ttanaman dan produk tanaman pangan hprtikultura, palawija
dan perkebunan , ternak : susu, telur, daging dan madu, pakan ternak.
3. Lembaga Sertifikasi Organik Inoffice, No. Sertifikat : OKPO LS-003
Alamat : Jalan Tentara Pelajar no.1, Bogor.
Telp : (0251)8382641
Email : inoffice@yahoo.com
Ruang Lingkup : produk segar : pangan, hortikultuira
4. Lembaga Serttifikasi Organsik Sumatera Barat, No. Sertifikat : OKPO LS-004
61
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Alamat : Jalan Raden Saleh No.4A, Padang, Telp. : (0751)26017
Ruang lingkup : Produk segra : pangan, hortikultura
5. Lembaga Sertifikasi Organik LeSOS No Sertifikat : OKPO-LS-005
Alamat : PO BOX 03 Trawas Mojokerto 61375 Telp. (0321) 618754
Ruang Lingkup : Produk Segar Tanaman dan produk Tanaman
6 Lembaga Sertifikasi BIOCert Indonesia No Sertifikat : OKPO-LS-006
Alamat : Komplek Budi Agung Jln. Kamper Blok M. No.1 Sukadamai-Bogor
Tlp/Fax. (0251) 8316294
Email : biocert@biocert.or.id
Ruang Lingkup: Tanaman dan produk tanaman, pangan, palawija, hortikultura,
rempah-rempah, pemasar dan restoran, peternakan, perikanan dan produk khusus
seperti jamur
7 Lembaga Sertifikasi Organik PERSADA No Sertifikat : OKPO-LS-007
Alamat : Jl. Nogorojo No 20 Komplek polri, Gowok, Depok, Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 488420 Fax. (0274) 889477
Ruang Lingkup : Tanaman dan produk tanaman : (pangan,palawija, hortikultura
dan perkebunan); Produk ternak dan hasil peternakan : (telur, daging, susu,susu
kambing dan madu) ; Produk-produk olahan tanaman dan ternak.
8. Lembaga Sertifikasi Organik Sustainable Development Service (SDS)
No, Sertifikasi : OKPO-LS-/0/08
Kantor Pusat : Jalan Letjen Suprapto XVIII No.7A, Kebonsari, Jember 68122,
Jawa Timur. Telepon : 0331-332864
9. LSO - Dinas Pertanian Propinsi.
Kelompok tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang telah
menyelesaikan tindakan perbaikan, dapat memgajukan sertifikasi ke LSO melalui
Dinas Pertanian Propinsi penerima dana dekonsentrasi.
62
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
4.6. Mengutamakan Agribisnis yang Berwawasan Lingkungan
Seiring dengan pentingnya menyelamatkan lingkungan, maka pilihan
agribisnis yang berwawasan lingkungan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.
Konsep agribisnis yang berwawasan lingkungan merupakan konsep agribisnis
yang telah umum diimplementasikan di negara – negara lain, terutama di negara
maju, yang tidak saja beorientasi kepada agribinis yang menerapkan manajemen
dengan penanganan komoditas pertanian yang baik dan memperoleh benefit,
namun lebih dari itu, konsep agribisnis masa kini adalah konsep agribisnis yang
berkelanjutan atau sustainable agribusiness.
Konsep agribisnis berkelanjutan merupakan respons terhadap ancaman
ekologi, sosial dan kesehatan di masyarakat modern yang disebabkan oleh
globalisasi dan pertumbuhan ekonomi beserta akibat dari keteledoran manusia di
masa lalu. Kini, konsep agribisnis yang secara benar dijalankan hendaknya yang
merespon ancaman-ancaman tersebut.
Menurut Wiśniewska (2015), agribisnis merupakan salah satu sektor
manufaktur terbesar di dunia dalam hal nilai output, pekerjaan dan perdagangan
internasional, yang terdiri dari : industri pra-produksi, pertanian, pengolahan
makanan, distribusi dan perdagangan. Fungsi utama agribisnis adalah
menghasilkan kuantitas dan kualitas makanan yang cukup untuk mempertahankan
populasi yang sehat. Tentu yang dimaksud sehat adalah, populasi yang terjamin
pangannya, atau dikatakan sebagai populasi yang mempunyai ketahanan pangan.
Meski agrobisnis merupakan salah satu sektor manufaktur terbesar di dunia,
namun sebanyak 815 juta manusia di dunia masih kekurangan pangan atau
kelaparan.(FAO, 2018),. Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20, tentu
63
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
kelaparan yang dialami oleh banyak orang itu menjadi salah satu tanggung jawab
bersama yang diembannya, bersama-sama dengan negara-negara lain. Namun
demikian, konsep agrobisnis berkelanjutan, hendaknya terus dicanangkan, sebab
keamanan pangan dan keanekaragaman hayati adalah hasil langsung dari
pembangunan berkelanjutan pada sektor agribisnis.
Wiśniewska (2015) juga menguraikan, selama dekade terakhir ini telah
menjadi jelas bahwa perkembangan ekonomi dan teknologi dalam agribisnis tidak
hanya memiliki pengaruh lingkungan, sosial dan kelembagaan, tetapi juga
memiliki antara lain konsekuensi gizi dan regional yang penting. Tujuan dan hasil
indikator pembangunan berkelanjutan lebih sering bersifat kualitatif daripada
kuantitatif ( Wiśniewska ,2015), namun apapun alasan itu, konsep agrobisnis yang
berkelanjutan layak terus dikembangkan. Sebab kerusakan lingkungan akibat ulah
manusia telah nyata merusak seluruh sudut kehidupan manusia, sehingga prinsip
berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan lingkungan, merupakan satu-
satunya jalan yang sudah tidak bisa ditawar lagi.
Adapun sebagai negara agraris, Indonesia patut menjalankan konsep
agribisnis yang mementingkan harkat hidup orang banyak, diantaranya mereka
yang hidup dari sektor pertanian sebanyak 31.86 % atau sedikitnya terdapat 39,86
juta orang yang bekerja di sektor pertanian di Indonesia pada 2017 (BPS dalam
Hamdani, 2017). . Meski prosentasenya terus menurun, namun berdasarkan
lapangan pekerjaannya, pada Februari 2017, penduduk Indonesia paling banyak
bekerja di sektor pertanian (BPS dalam Hamdani, 2017).
Dengan melaksanakan usaha pertanian dengan menggunakan konsep
agribisnis maka diharapkan usaha-usaha pertanian akan dapat diperbaiki sehingga
64
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
tercapai peningkatan produk, baik kualitas maupun kuantitas sehingga kebutuhan
dan kepuasan masyarakat akan pangan relatif terpenuhi, terutama bagi golongan
yang masuk dalam kondisi rawan pangan. Perlu diketahui, Indonesia mempunyai
kategori kelaparan di tingkat serius, yakni 19 juta orang yang kekurangan gizi (
Naelufar, 2017). Namun demikian, GHI (Global Hunger Index) Indonesia terus
menurun dari tahun ke tahun, yakni : 35 % (1992), 25 % (2000), 28 % (2008), dan
22% (2016) (Naelufar, 2017), Sehubungan hal tersebut, penerapan konsep
manajemen agribisnis sudah saatnya diterapkan dengan baik, agar produktivitas
pertanian meningkat, yang tentunya sangat berguna bagi mereka yang
membutuhkan kecukupan pangan. Selain itu pula, distribusi pangan yang belum
merata, menyebabkan kerawanan gizi masih terjadi. Prinsip manajemen rantai
pasok atau Supply Chain Management tidak saja diterapkan pada tingkat industri,
tetapi dari hulu ke hilir sudah harus diimplementasikan. Jika prinsip manajemen
ini juga dijalankan seiring dengan penerapan manajemen agribisnis, niscaya
semua sektor yang terkait akan terus bertumbuh. Prinsip manajemen rantai pasok
itu adalah, setiap titik dalam berproses memproduksi produk hingga
mendistribusikannya sampai ke tangan konsumen, mempunyai porsi yang adil
bagi masing-masing titik. Konsumen pun berhak memperoleh harga wajar yang
dibayarkan saat mereka membelinya. Dengan berkembangnya teknologi
informasi, tidak ada alasan bagi setiap orang untuk tidak mengetahui berapa
modal yang dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk hingga sampai
konsumen membelinya. Petani berhak memperoleh harga yang setimpal dengan
usahanya menumbuhkan, memelihara hingga panen tiba. Jika petani lemah, maka
65
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
pihak yang kuat mengkokohkannya, sehingga ia tidak rubuh. Petani Indonesia
masih diselimuti dengan berbagai keterbatasan , seperti :
(1) Pendidikan yang terbatas, sehingga pengetahuan yang kurang luas
menyebabkan mutu sumberdaya manusia yang rendah
(2) Kepemilikan lahan pun tidak luas
(3) Kelembagaan yang seharusnya mengkokohkan kedudukan petani, seperti
KUD, kurang kuat, sehingga tidak mampu melindungi petani.
(4) Penerapan teknologi tidak berfokus kepada kebutuhan teknologi bagi petani,
sehingga penerapakn IPTEK dinilai menurun
(5) Agribisnis belum berkembang di semua divisi pertanian
(6) Permodalan yang tidak mudah didapat oleh petani
(7) Daya saing produk yang lemah, karena kurangnya promosi dan kondisi hasil
pertanian yang kurang berkualitas.
(8) Infrastruktur di beberapa lokasi masih kurang membantu pihak petani
(9) Pemetaan produk berpotensi masih belum tertata baik
Hal-hal yang diuraikan di atas, kiranya dapat menjadi informasi dalam
menggali potensi produk pertanian, memberdayakannya sehingga memperoleh
nilai tambah dan mendorong bertumbuhnya sektor pertanian, dengan tetap
memperhatikan keselamatan lingkungan di masa depan.
Contoh dalam penerapan Manajemen Agribisnis yang berkelanjutan
adalah dengan menerapkan sistem pertanian organik.
Departemen Pertanian telah meluncurkan pedoman dalam bertani secara organik ,
dengan ketentuan-ketentuan yang cukup detil.
66
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Husain dkk (2005) mempertanyakan, mungkinkan pertanian organik
dibudidayakan di Indonesia? Tentu saja sangat mungkin, yang dibuktikan
berkembangnya Lembaga-lembaga Sertifikasi Organik (LSO) saat ini berjumlah 8
buah. Hal ini seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, edukasi
yang terus menerus dilakukan dan naiknya tingkat pendapatan masyarakat yang
tidak keberatan membelanjakan produk organik dengan harga yang lebih tinggi
dari tanaman lain pada umumnya.
Namun demikian, Widotono (2016) menguraikan kerumitan sertifikasi
organik sebagai berikut :
1. Mengacu kepada ketentuan CAC (Codex Alimentarius Commission) atau
IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)
2. Negara pengimpor memiliki aturan tersendiri, seperti Jepang memiliki
Japanese Agricultural Sandard (JAS), Amerika Serikat memiliki National Organic
Standards (NOS), dan Uni Eropa Organic Farming, Korea : CAC, China IFOAM,
CAC, India CAC, IFOAM, EU, Thailand CAC,
Malaysia CAC, dll.
3. Biaya cukup besar bagi petani Indonesia
Sewaktu mengajukan permohonan, operator melampirkan:
(a) Formulir Pendaftaran dan Pendataan dari lembaga sertifikasi yang mencakup
identitas perusahaan dan data umum perusahaan serta
(b) Rencana Kerja Jaminan Mutu Produk pangan organik
Rencana Kerja Jaminan Mutu Produk pangan organik
Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan sertifikasi maka operator harus
menetapkan, menerapkan dan menjaga produk organik yang sesuai dengan ruang
67
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
lingkup kegiatannya. Dalam hal ini operator harus mendokumentasikan kebijakan,
sistem, program, prosedur, dan instruksi sejauh diperlukan untuk menjamin mutu
produk organiknya. Dokumentasi sistem ini harus dikomunikasikan kepada,
dimengerti oleh, tersedia bagi, dan diterapkan oleh semua personil yang terkait
dalam operator yang dikerjakan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang
barkaitan dengan persyaratan manajemen dan persyaratan teknis sebagai berikut:
1. Persyaratan manajemen
Persyaratan manajemen pada suatu sistem merupakan hal yang mutlak
diperlukan. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen dapat
berjalan secara efektif dan efisien, berkelanjutan, serta selalu berkembang lebih
baik. Persyaratan ini pada umumnya bersifat universal sehingga lazim disebut
sebagai “Universal Program”. Berikut adalah beberapa persyaratan manajemen
dalam rangka penerapan sertifikasi produk pangan organik berdasarkan acuan-
acuan normatif di atas:
1.1 Kebijakan Mutu
Operator seyogyanya mempunyai kebijakan mutu tentang produksi dan
pemasaran pangan organik yang ditetapkan dan diterapkan di lingkungan
usahanya untuk menciptakan jaminan mutu produk organik yang tinggi.
Kebijakan mutu sebaiknya mencakup tujuan, sumberdaya yang digunakan, dan
alasan manajemen jaminan mutu yang digunakan.
1.2 Organisasi
Badan usaha harus menjelaskan struktur organisasi yang dipunyai serta
menjelaskan tentang kebijakan mutu dan uraian tugas masing-masing bagian.
Dalam hal penanganan produk organik, badan usaha seyogyanya mempunyai satu
68
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
unit khusus dalam organisasi yang bertanggungjawab terhadap Dokumen
Penerapan Jaminan Mutu produk pangan organik yang dihasilkan. Anggotanya
harus terdiri dari divisidivisi manajemen dalam badan usaha, serta mempunyai
latar belakang pertanian sesuai bidangnya, biologi, ilmu pangan serta ilmu-ilmu
lain yang relevan.
1.3 Personil
Menyebutkan personil yang bertanggungjawab untuk mengembangkan,
menerapkan, memutakhirkan, merivisi, dan mendistribusikan Dokumen
Penerapan Jaminan Mutu produk organik serta proses penyelesaiannya.
Menyajikan cara memelihara rekaman data yang memuat program dan
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman personil badan usaha.
Menguraikan hal-hal lain bagi personil badan usaha yang ditujukan untuk
meningkatkan kinerja personil seperti pelatihan internal.
1.4 Pengendalian dokumen.
Operator harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalian
semua dokumen yang merupakan bagian dari sistem, seperti peraturan, standar,
atau dokumen normatif lain, metode produksi dan pengawasan, demikian juga
gambar, perangkat lunak, spesifikasi, instruksi dan panduan. Semua dokumen
yang diterbitkan untuk personil di kumpulkan pada operator yang merupakan
bagian dari sistem mutu yang harus dikaji ulang dan disahkan oleh personil yang
berwenang sebelum diterbitkan. Prosedur yang diberlakukan harus dipastikan
bahwa:
a) edisi resmi dari dokumen yang sesuai tersedia disemua lokasi tempat dilakukan
kegiatan yang penting bagi efektivitas fungsi produk pangan organik.
69
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
b) dokumen dikaji ulang secara berkala, dan bila perlu, direvisi untuk memastikan
kesinambungan kesesuaian dan kecukupannya terhadap persyaratan yang
diterapkan,
c) dokumen Penerapan Jaminan Mutu harus diidentifikasi secara khusus yang
mencakup tanggal penerbitan dan/atau identifikasi revisi, penomoran halaman,
jumlah keseluruhan halaman atau tanda yang menunjukkan akhir dokumen, dan
pihak berwenang yang menerbitkan.
1.5 Pembelian jasa dan perbekalan
Operator harus mempunyai suatu kebijakan dan prosedur untuk memilih
dan membeli jasa dan perbekalan yang penggunaannya mempengaruhi mutu
produk pangan organik. Harus ada prosedur untuk pembelian, penerimaan dan
penyimpanan bahan-bahan substansi input dan peralatan yang relevan dengan
kegiatan Produk pangan organik. Rekaman dari tindakan yang dilakukan untuk
mengecek kesesuaian harus dipelihara. Dokumen pembelian barang-barang yang
mempengaruhi mutu produk pangan organik harus berisi data yang menjelaskan
jasa dan perbekalan yang dibeli. Dokumen pembelian harus dikaji ulang dan
disahkan spesifikasi teknisnya terlebih dahulu sebelum diedarkan. Operator harus
mengevaluasi pemasok bahan habis pakai, perbekalan, dan jasa yang penting dan
berpengaruh pada mutu produk pangan organik, dan harus memelihara rekaman
evaluasi tersebut serta membuat daftar yang disetujui.
1.6 Pengaduan
Operator harus mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan
pengaduan yang diterima dari pelanggan atau pihak-pihak lain. Rekaman semua
70
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
pengaduan dan penyelidikan serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh
operator harus dipelihara.
1.7 Pengendalian produk yang tidak sesuai
Operator harus mempunyai suatu kebijakan dan prosedur yang harus
diterapkan bila terdapat aspek apapun dari pekerjaan produk pangan organik yang
dilakukan, atau produk pangan organik tidak sesuai dengan prosedur, standar, atau
peraturan teknis serta persyaratan pelanggan yang telah disetujui. Kebijakan dan
prosedur harus memastikan bahwa:
a) Tanggungjawab dan kewewenangan untuk pengelolaan pekerjaan/produk tidak
sesuai ditentukan dan tindakan (termasuk menghentikan pekerjaan dan menahan
produk) ditetapkan dan dilaksanakan bila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai;
b) Evaluasi dilakukan terhadap signifikansi ketidaksesuaian pekerjaan/produk;
c) Tindakan perbaikan segera dilakukan bersamaan dengan keputusan
pekerjaan/produk yang ditolak atau yang tidak sesuai;
d) Bila diperlukan, pelanggan diberitahu dan pekerjaan dibatalkan;
e) Tanggung jawab untuk menyetujui dilanjutkannya kembali pekerjaan harus
ditetapkan.
1.8 Tindakan perbaikan
Operator harus menetapkan kebijakan dan prosedur serta harus
memberikan kewenangan yang sesuai untuk melakukan tindakan perbaikan bila
pekerjaan yang tidak sesuai atau penyimpangan kebijakan dan prosedur di dalam
sistem yang ditetapkan. Prosedur tindakan perbaikan harus dimulai dengan suatu
penyelidikan untuk menentukan akar permasalahan. Apabila tindakan perbaikan
perlu dilakukan, operator harus mengidentifikasi tindakan perbaikan yang
71
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
potensial. Tindakan perbaikan harus dilakukan sampai sistem dapat berjalan
kembali secara efektif, dan didokumentasikan.
1.9 Tindakan pencegahan
Penyebab ketidaksesuaian yang potensial, baik teknis maupun manajemen,
harus diidentifikasi. Jika tindakan pencegahan diperlukan, rencana tindakan
Persoalan ekspor pangan organik bukan tanpa kendala, hampir tiap negara
memiliki aturan main impor yang sangat ketat
Indonesia sebenarnya tidak terlalu tertinggal dengan dibuktikannya kebun
pertanian organik Agatho di Cisarua sudah lebih 10 tahun eksis dalam sistim
pertanian organik pada 2005( Husain dkk, 2005) , namun jika dibanding Jepang,
Belanda, Perancis, Itali, Amerika, dll, tentu kemajuan pertanian organik di
Indonesia masih cukup jauh dari modern. .
Pola pertanian organik modern sangat berbeda dengan pertanian alamiah
di jaman dulu. Dalam pertanian organik modern dibutuhkan teknologi bercocok
tanam, penyediaan pupuk organik, pengendalian hama dan penyakit dengan
menggunakan agen hayati atau mikroba serta manajemen yang baik untuk
kesuksesan pertanian organik tersebut. Di Indonesia, diperkirakan terdapat 40,000
ha pertanian organik, termasuk lahan alami dan kebun campuran dan untuk
kawasan Asia, Indonesia mempunyai potensi besar sebanyak 43.000 kebun
organik ( Husain dkk, 2005).
Selain aspek lahan, aspek pengelolaan pertanian organik dalam hal ini
terkait dengan teknik budidaya juga perlu mendapat perhatian tersendiri. Sebagai
salah satu contoh adalah teknik bertani sayuran organik, seperti diuraikan di
bawah ini.
72
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
•Tanaman ditanam pada bedengan-bedengan dengan ukuran bervariasidisesuaikan
dengan kondisi lahan
•Menanam strip rumput di sekeliling bedengan untuk mengawetkan tanah dari
erosi dan aliran permukaan
•Mengatur dan memilih jenis tanaman sayuran dan legum yang sesuai untuk
sistem tumpang sari atau multikultur seperti contoh lobak, bawang daun dengan
kacang tanah dalam satu bedengan.
•Mengatur rotasi tanaman sayuran dengan tanaman legum dalam setiap musim
tanam. Mengembalikan sisa panen/serasah tanaman ke dalam tanah (bentuk segar
atau kompos).
•Memberikan pupuk organik (pupuk hijau, pupuk kandang, dan lainnya), hingga
semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman menjadi tersedia.
•Menanam kenikir, kemangi, tephrosia, lavender, dan mimba di antara bedengan
tanaman sayuran untuk pengendalian hama dan penyakit.
•Menjaga kebersihan areal pertanaman.
Dalam pertanian organik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
secara umum adalah mengikuti aturan berikut:
•Menghindari benih/bibit hasil rekayasa genetika. Sebaiknya benih berasal dari
kebun pertanian organik,
•Menghindari penggunaan pupuk kimia sintetis, zat pengatur tumbuh, pestisida.
Pengendalian hama dilakukan dengan cara mekanis, biologis dan rotasi tanaman,
•Peningkatan kesuburan tanah dilakukan secara alami melalui penambahan
pupuk organik, sisa tanaman, pupuk alam, dan rotasi dengan tanaman legum.
73
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Penanganan pasca panen dan pengawetan bahan pangan menggunakan cara-cara
yang alami.
Permasalahan dalam pertanian organik umumnya adalah :
a. Penyediaan pupuk organik
Permasalahan pertanian organik di Indonesia sejalan dengan perkembangan
pertanian organik itu sendiri. Pertanian organik mutlak memerlukan pupuk
organik sebagai sumber hara utama. Dalam sistem pertanian organik, ketersediaan
hara bagi tanaman harus berasal dari pupuk organik. Padahal dalam pupuk
organik tersebut kandungan hara per satuan berat kering bahan jauh dibawah
realis hara yang dihasilkan oleh pupuk anorganik, seperti Urea, TSP dan KCl,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar tanaman (minimum crop requirement)
cukup membuat petani kewalahan. Sebagai ilustrasi, untuk menanam sayuran
dalam satu bedengan seluas 1 x 10 m saja dibutuhkan pupuk organik (kompos)
sekitar 25 kg untuk 2 kali musim tanam atau setara dengan 25 ton/ha.
Bandingakan dengan penggunaan pupuk anorganik Urea TSP dan KCl yg hanya
membutuhkan total pemupukan sekitar 200-300 kg/ha. Karena memang umumnya
petani bukan petani mampu yang memiliki lahan dan ternak sekaligus, sehingga
mereka mesti membeli dari sumber lainnya dan inimembutuhkan biaya yang
cukup tinggi disamping tenaga yang lebih besar.
b. Teknologi pendukung
Setelah masalah penyediaan pupuk organik, masalah utama yang lain
adalah teknologi budidaya pertanian organik itu sendiri. Teknik bercocok tanam
yang benar seperti pemilihan rotasi tanaman dengan mempertimbangkan
74
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
efek allelopati dan pemutusan siklus hidup hama perlu diketahui. Pengetahuan
akan tanaman yang dapat menyumbangkan hara tanaman seperti legum sebagai
tanaman penyumbang Nitrogen dan unsur hara lainnya sangatlah membantu untuk
kelestarian lahan pertanian organik. Selain itu teknologi pencegahan hama dan
penyakit juga sangat diperlukan, terutama pada pembudidayaa pertanian organik
di musim hujan.
c. Pemasaran
Pemasaran produk organik didalam negeri sampai saat ini hanyalah
berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak, konsumen dan produsen. Sedangkan
untuk pemasaran keluar negeri, produk organik Indonesia masih sulit menembus
pasar internasional meskipun sudah ada beberapa pengusaha yang pernah
menembus pasar international tersebut. Kendala utama adalah sertifikasi produk
oleh suatu badan sertifikasi yang sesuai standar suatu negara yang akan di tuju.
Akibat keterbatasan sarana dan prasarana terutama terkait dengan standar mutu
produk, sebagian besar produk pertanian organik tersebut berbalik memenuhi
pasar dalam negeri yang masih memiliki pangsa pasar cukup luas. Hal yang
banyak terjadi adalah masing-masing melabel produknya sebagai produk organik,
namun kenyatannya banyak yang masih mencampur pupuk organik dengan pupuk
kimia serta menggunakan sedikit pestisida. Petani yang benar-benar
melaksanakan pertanian organik tentu saja akan merugi
Pasar produk organik didunia masih dikuasai Amerika dan Eropa,
sedangkan di Asia Negara Asia dan kawasan lainnya hanya menyumbang sekitar
3%.
d. Kesalahan Persepsi
75
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Masyarakat awam menganggap produk organik adalah produk yang bagus
tidak hanya dari segi kandungan nutrisi namun juga penampilan produknya.
Kenyataannya produk organik itu tidaklah selalu bagus, sebagai contoh daun
berlobang dan berukuran kecil, karena tidak menggunakan pestisida dan zat
perangsang tumbuh atau pupuk anorganik lainnya. Pada tahun awal hasil
pertaniann belum memberikan produk yang sesuai harapan.
Sebagian petani terbiasa menggunakan pupuk an organik yang akan
memberikan respon cepat pada tanaman. Seperti misalnya pemupukan Urea akan
menghasilkan tanaman yang pertumbuhannya cepat, sementara dengan
pemupukan organik pengaruh perubahan pertumbuhan tanaman tergolong lambat.
Baru pada musim ketiga dan seterusnya, efek pupuk organik tersebut
menunjukkan hasil yang nyata perbedaannya dengan pertanian non organikm
sehingga dapat disimpulkan pertanian organik di tahun-tahun awal akan
mengalami banyak kendala dan membutuhkan modal yang cukup untuk bertahan.
e. Sertifikasi dan Standarisasi
Beberapa lembaga standarisasi pertanian organik adalah sebagai berikut:
1. Standar Internasional
Standar IFOAM. Standar dasar untuk produk organik dan prosesnya dari IFOAM
sejak 1980. The Codex Alimentarius. Standar yang disusun dengan penyesuaian
standar IFOAM dengan beberapa standar dan aturan lain.
2. National dan supranational regional
3. Standard setiap negara
Departemen Pertanian juga telah menyusun standar pertanian organik di
Indonesia, tertuang dalam SNI 01-6729-2002. Sistim pertanian organik menganut
76
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
paham organik proses, artinya semua proses sistim pertanian organik dimulai dari
penyiapan lahan hingga pasca panen memenuhi standar budidaya organik, bukan
dilihat dari produk dasar bagi lembaga sertifikasi yang nantinya juga harus di
akreditasi oleh Deptan melalui PSA (Pusat Standarisasi dan Akreditasi).
Pedoman produksi di Indonesia diatur oleh Pemerintah dengan aturan SNI ,
termasuk produk pangan organik. Sistem pangan organik disusun dengan
mengadopsi seluruh materi dalam dokumen standar CAC/GL 32 – 1999. Pedoman
tersebut melingkupi memproduksi, memproses, melabel, dan memasarkan produk
pertanian organik serta medimodifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia.
Namun dengan aturan yang ketat, dengan melihat kondisi petani di Indonesia,
hampir tidak mungkin mereka mendapatkan label sertifikasi dari suatu lembaga
sertifikasi asing maupun dalam negri. Luasan lahan yang dimiliki serta biaya
sertifikasi yang tidak terjangkau, menyebabkan mereka tidak mampu
mensertifikasi lahannya. Satu-satunya jalan adalah membentuk suatu kelompok
petani organik dalam suatu kawasan yang luas yang memenuhi syarat sertifikasi,
dengan demikian mereka dapat melaksanakan pembiayaan sertifikasi usaha tani
mereka secara gotong royong. Namun ini pun masih sangat tergantung pada
kontinuitas produksi
mereka.
5. Tantangan Pertanian Organik, di bidang Riset, Ekonomi dan Lingkungan
Berbagai permasalahan seputar pertanian organik dapat diatasi dengan
kesungguhan petani dengan bantuan pemerintah dalam memfasilitasinya, dengan
demikian diharapkan sistem pertanian organik dimasa yang akan datang dapat
berkembang menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan pangan dalam
77
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
negeri. Untuk itu diperlukan penelitian mendalam terhadap sistim pertanian
organik ini. Banyak bidang penelitian yang terkait dalam mendukung
perkembangan pertanian organik. Dimulai dari kajian tentang penyediaan mikroba
yang dapat mendekomposisi bahan organik dalam waktu singkat, sehingga
penyediaan pupuk organik dapat terpenuhi Kemudian pengetahuan tentang
kesesuaian tanaman yang ditanam secara multikultur, dan pemutusan siklus hama
dengan rotasi tanaman. Hingga saat ini belum ada hasil penelitian yang dapat
menjelaskan hal tersebut, petani hanya mencoba-coba dari beberapa kali
pengalaman mereka bercocok tanam tersebut. Pengendalian hama dan penyakit
tanaman secara alami merupakan hal terberat dalam sistim pertanian. Kegagalan
panen merupakan ancaman besar buat petani, sehingga sangat dibutuhkan riset
tentang bahan alami yang mengandung bahan insektisida dan penerapannya dalam
pertanian. Pengetahuan akan perbaikan lahan dengan sistim pertanian organik
sudah diketahui, namun sejauh mana sistim ini menjaga keberlangsungan lahan
pertanian perlu diketahui melalui penelitian neraca hara dalam jangka waktu
panjang. Kajian di segi pemasaran dan ekonomi juga akan sangat berperan dalam
menembus pasar internasional produk organik Indonesia.
Perkembangan pertanian organik di Indonesia dapat menjadi suatu
alternatif pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dalam jangka panjang.
Sasaran jangka pendek dari sistim pertanian organik ini adalah kesadaran
masyarakat dan petani akan perlunya melestarikan lahan dan menjaga lingkungan
dengan mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis seperti pupuk kimia dan
pestisida dan berusaha semampunya memanfaatkan bahan-bahan alami disekitar
mereka. Dan untuk jangka panjang, potensi pasar produk organik di dunia terbuka
78
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
lebar bagi Indonesia. Namun demikian potensi lahan yang dapat dijadikan lahan
pertanian organik sangat kecil. sehingga lahan pertanian non organik masih
menjadi andalan produksi pangan di Indonesia, namun setidaknya kebutuhan
pasar akan produk organik dapat terpenuhi.
79
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
V. PENTINGNYA SUMBERDAYA MANUSIA DALAM AGRIBISNIS
Sebagaimana telah diketahui, sebagian besar petani Indonesia mempunyai
kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM) yang terbatas, sehingga memerlukan
pelatihan profesionalisme usaha, pendidikan manajemen, pelatihan pemasaran dan
lain-lain. Kesenjangan kualitas SDM yang ada dengan yang dibutuhkan, semakin
terasa melebar, yang membutuhkan penanganan segera. Pengetahuan tentang
pertanian modern dengan kemampuan (skill) dalam manajemen di sektor
pertanian, akan menjadi semakin besar seiring dengan berkembangnya agribisnis
yang berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian,
peningkatan SDM di sektor pertanian tidak hanya terbatas pada aspek teknis
budidaya, tetapi juga aspek lain dalam sistem agribisnis.
Hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah bukan seberapa besar
modal yang dibutuhkan, namun penting untuk mengetahui seberapa jauh petani
Indonesia mengelola agribisnis dalam mengembangkan usaha. Oleh karena itu,
dibutuhkan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan petani selaku pelaku
agribisnis berskala kecil dalam memulai usaha mereka dengan pendampingan
yang tepat sebagai suatu upaya meningkatkan usaha di sektor pertanian.
Dalam menghadapi perkembangan usaha yang kini dikenal sebagai start-
up business, kiranya diperlukan suatu upaya pendampingan yang tepat agar
agribisnis di Indonesia dapat berkembang sebagaimana diharapkan.
80
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
VI. AGROBISNIS DI INDONESIA
Sektor pertanian memainkan peran strategis dalam proses pembangunan
ekonomi suatu negara yang berbasis pertanian. Negara-negara maju telah
membuktikan bahwa sektor pertanian telah membuat kontribusi yang signifikan
bagi kemakmuran ekonomi dan pembangunan dalam negeri.(Pragyandeepa,
2019). Selanjutnya diuraikannya, bahwa jika sebuah negara dengan pendapatan
riil per kapita rendah, maka hal yang perlu ditekankan adalah perhatian pada
sektor pertanian dan industri primer. Pragyadeepa (2019) mengutip pernyataan
Dr. Bright Singh sebagai berikut :
“Peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan per kapita
masyarakat pedesaan, bersama dengan industrialisasi dan urbanisasi,
menyebabkan peningkatan permintaan dalam industri”
Ia kemudian mengungkapkan sejarah kesuksesan Inggris, yang berawal dari
adanya revolusi pertanian sebelum terjadinya revolusi industri di sana. Bahkan di
AS dan Jepang, pembangunan pertanian juga telah membantu proses
industrialisasi mereka. Demikian pula, di berbagai negara dunia yang kurang
berkembang, kini bukan saja proses keterbatasan penekanan yang berlebihan pada
industrialisasi sebagai cara untuk memperoleh pendapatan riil per kapita yang
lebih tinggi, namun sektor pertanian dan industri yang saling melengkapi dan
saling mendukung itulah yang penting, sebagaimana hubungan input dan output.
Oleh karenanya tidak mengherankan bahwa peningkatan hasil pertanian dan
produktivitasnya, cenderung memberikan kontribusi besar pada perkembangan
ekonomi negara secara keseluruhan, sehingga menurut Pragyadeepa (2019), akan
81
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
lebih rasional dan pantas untuk memberikan penekanan lebih besar pada
pengembangan lebih lanjut pada sektor pertanian.
Pragyadeepa (2019) menguraikan selanjutnya beberapa pendapat dari
Kinderberger, Todaro, Lewis dan Nurkse dll., bahwa pertanian memberi
kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dalam beberapa cara, yaitu:
(1) penyedia kebutuhan pangan masyarakat.
(2) penyedia bahan baku untuk sektor pertanian berbasis industri
(3) penyedia lapangan pekerjaan karena adanya industri sektor pertanian dan
dapat menyerap tenaga kerja yang tidak berpendidikan, terbelakang dan tidak
terampil
(4) menciptakan permintaan barang-barang yang diproduksi yang dapat
dikonsumsi masyarakat pedesaan sesuai dengan kemampuan daya beli mereka.
(5) Dengan diperolehnya surplus, maka dapat diinvestasikan dalam bentuk
tabungan dan pajak untuk diinvestasikan pada sektor non-pertanian.
(6) mendapatkan devisa melalui ekspor produk pertanian dan non7 pertanian.
(7) Tanaman, pohon dan sejenisnya, perlu terus dilestarikan agar tercipta
ekosistem yang bermanfaat bagi lingkungan.
(8) Jika terjadi pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaaan, maka akan
terjadi pemerataan ekonomi hingga pelosok pedesaan, sehingga dapat
meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).
Oleh karenanya, jika proses pembangunan ekonomi akan dimulai dan
dibuat mandiri, maka harus dimulai dari sektor pertanian.
82
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Hal penting yang selalu diingat adalah sektor pertanian merupakan tulang
punggung ekonomi yang menyediakan bahan-bahan dasar bagi umat manusia dan
juga bahan mentah untuk industrialisasi.
Oleh karena itu, peran pertanian untuk pengembangan ekonomi dapat
dinyatakan sebagai berikut:
1. Sektor pertanian memberi kontribusi terhadap Pendapatan Nasional:
Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah ekonomi di banyak negara maju,
menunjukkan bahwa kemakmuran pertanian berkontribusi besar dalam
mendorong kemajuan ekonomi. Negara-negara industri terkemuka saat ini
dulunya didominasi dari sektor pertanian sementara negara-negara berkembang
masih memiliki dominasi pertanian dan sebagian besar berkontribusi terhadap
pendapatan nasional. Di India, masih 28% dari pendapatan nasional berasal dari
sektor ini (Pragyadeepa, 2019)
2. Sumber Pasokan Makanan:
Pertanian adalah sumber dasar pasokan makanan dari semua negara di dunia
— baik yang terbelakang, berkembang atau bahkan maju. Hal ini berkaitan
dengan populasi di negara itu sehingga pangan harus tercukupi. Jika jumlah
penduduk meningkat, maka kebutuhan pangan juga mengalami kenaikan sehingga
memberi tekanan berat kepada negara-negara terbelakang dan berkembang karena
peningkatan permintaan makanan dengan cepat. Jika pertanian gagal memenuhi
kenaikan permintaan makanan, maka hal itu akan berdampak buruk terhadap laju
pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pasokan makanan oleh sektor pertanian,
karenanya, sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
83
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Pragyadeepa (2019) mengungkapkan, peningkatan permintaan makanan dalam
suatu perekonomian ditentukan oleh persamaan berikut:
D = P + 2g
Dimana : D = Tingkat Pertumbuhan Tahunan dalam permintaan
makanan.
P = Population Growth Rate.
g = Tingkat Peningkatan Pendapatan per Kapita.
2 = merupakan Elastisitas Pendapatan dari Permintaan
untuk Produk Pertanian.
3. Penyedia Bahan Baku bagi Agro Industri
Kemajuan pertanian diperlukan untuk meningkatkan pasokan bahan baku
bagi industri berbasis pertanian. khususnya di negara-negara berkembang.
Kekurangan produk pertanian berdampak pada produksi industri pangan dan
sebagai akibatnya, terjadi kenaikan tingkat harga barang-barang lainnya ( harga
umum ). Hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.
Contoh produk-produk berbasis produk pertanian adalah : pabrik tepung beras,
tepung sagu, pemipil jagung, pabrik minyak, pabrik roti, rumah potong daging,
pabrik susu, keju, pabrik gula, pabrik karung goni, pabrik tekstil dan banyak
industri lainnya didasarkan pada produk pertanian.
4. Memungkinkan Ekspor
Kemajuan di sektor pertanian memberikan surplus untuk meningkatkan ekspor
produk pertanian.
84
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Dengan demikian, maka peranan produk agribisnis dalam perekonomian dan
pembangunan Indonesia memang cukup besar dan memberi potensi terhadap
kemajuan perekonomian bangsa.
Kontrbusi sektor pertanian dan agribisnis terhadap perekonomian nasional
terutama terhadap PDB Nasional, ekspor dan penyerapan tenaga kerja..
di Indonesia. Sektor pertanian juga sangat berperan dalam pembangunan
perkekonomian suatu daerah, sebagai sumber pendapatan, sebagai sarana untuk
berusaha, serta sebagai sarana untuk dapat merubah nasib ke arah yang lebih baik
lagi. Peranan pertanian/agribisnis tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan
ekonomi petani dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut
telah terbukti pada sektor pertanian di Indonesia. Dengan tanah subur yang luas
dan berlimpah, Indonesia merupakan adalah salah satu produsen utama global dari
berbagai produk pertanian pertanian, seperti minyak kelapa sawit, cokelat, kopi,
karet dan lain-lain. Sumbangan sektor pertanian kepada produk domestik bruto
(PDB) Indonesia memang sedang telah menurun tajam selama lima dekade
terakhir, namun sektor pertanian masih memberikan pemasukan bagi mayoritas
rumah tangga Indonesia saat ini (Anonymous, 2019). Dirincikannya, pada 2012
sektor ini mempekerjakan sekitar 49 juta orang Indonesia, yang mewakili 41
persen dari total angkatan kerja Indonesia. Tetapi meskipun dalam jumlah absolut
tenaga kerja pertanian terus tumbuh, bagian relatifnya dari total tenaga kerja
Indonesia telah menurun secara signifikan dari 55 persen pada 1980-an menjadi
45 persen pada 1990-an dan saat ini menjadi 41 persen (Anonymousc, 2019).
Diuraikannya, selama krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, bagian ini tumbuh
secara signifikan karena pengangguran di sektor industri dan jasa diserap oleh
85
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
sektor pertanian (sebagian besar secara informal) dan antara pertengahan 1960-an
dan pertengahan 1980-an persentase luas tanah Indonesia yang digunakan untuk
pertanian tetap konstan di sekitar 21 persen dari total luas tanah Indonesia.
Namun, pada pertengahan 1980-an jumlah ini naik hampir 25 persen hingga akhir
1990-an. Mulai dari tahun 1998, peningkatan lainnya (karena pendirian
perkebunan skala besar - khususnya minyak kelapa sawit) membuat angka ini
mencapai level saat ini yaitu 30 persen (Anonymousc, 2019).
Tabel 1. Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Kenaikan(%) 2.9 3.0 4.0 3.4¹ 2.4¹
Sumber: : Bank Dunia dalam Anonymousc, 2019.
Sektor pertanian Indonesia terdiri dari perkebunan besar (milik negara dan
swasta) dan model produksi petani kecil sebagai perkebunan rakyat.. Perkebunan
besar cenderung berfokus pada komoditas yang merupakan produk ekspor penting
(kelapa sawit, dan karet), sedangkan petani plasma fokus pada beras, kedelai,
jagung, buah-buahan dan sayuran (Anonymousc, 2019).
Produk pertanian terpenting Indonesia adalah (Anonymousc, 2019):
• Minyak kelapa sawit
• Karet
• Biji cokelat
• Kopi
• Teh
• Singkong
• Beras
• rempah-rempah tropis
86
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
6.1. Minyak Kelapa Sawit
Minyak sawit merupakan sebuah contoh terbaik dari pengelolaan
agribisnis di Indonesia dan diharapkan komoditi lainnya dapat menjadi sukses
sebagaimana kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak yang
paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia (Anonymousc, 2019).
Diuraikannya, bahwa minyak ini murah, mudah diproduksi dan sangat stabil
untuk digunakan berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan
juga bisa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Kebanyakan minyak
sawit diproduksi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan karena pohon kelapa sawit
membutuhkan suhu hangat, sinar matahari, dan curah hujan tinggi untuk
memaksimalkan produksinya. Selanjutnya dijelaskan, efek samping yang negatif
dari produksi minyak sawit - selain dampaknya kepada kesehatan manusia karena
mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi - adalah fakta bahwa bisnis minyak
sawit menjadi penyebab utama penggundulan hutan di negara-negara seperti
Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak
sawit terbesar di dunia, sekaligus ia merupakan penghasil gas emisi rumah
kaca terbesar setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika
Serikat (AS). Informasi selanjutnya dikatakan bahwa produksi minyak sawit
dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total
menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia dan
Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar. Oleh
karenanya, tidaklah mengherankan bahwa saat ini, kelapa sawit merupakan
tanaman komersial terpenting di Indonesia. Pada 2014, Indonesia menghasilkan
33,5 juta ton minyak kelapa sawit dan menghasilkan $ 18,9 miliar dalam
pendapatan ekspor (Shibao, 2015). Hal ini menjadikan minyak kelapa sawit
87
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
sebagai ekspor ketiga yang paling bernilai di Indonesia, setelah batu bara dan gas
bumi (Anonymousd, 2015). Namun, kenaikan minyak sawit Indonesia hanya
fenomena yang relatif baru. Bagan di bawah ini menunjukkan pertumbuhan luar
biasa yang ditampilkan industri selama 30 tahun terakhir..
Gambar 2.Jumlah Tanaman Kelapa Sawit (ha) dan Produksinya (ribuan ton)
Sumber : Shibao, 2015
.
88
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Kenaikan industri kelapa sawit Indonesia adalah hasil dari kombinasi,
beberapa faktor-faktor diantaranya hasil perkebunan kelapa sawit rakyat yang
juga relatif tinggi. . Kelapa sawit adalah tanaman yang sangat produktif,
menghasilkan minyak 7 kali lebih banyak daripada minyak lobak dan 11 kali
lebih banyak dari kedelai per hektar. (Yusuf dalam Shibao, 2015).. Selain itu,
minyak sawit berkualitas tinggi dan sangat fleksibel (WWF dalam Shibao, 2015).
Minyak kelapa sawit sekarang digunakan sebagai basis sebagian besar bahan
makanan seperti margarin, juga sabun, lipstik dan juga dapat ditemukan pada
berbagai makanan hasil industri, minyak goreng, es krim, pelumas industri, dan
berbagai produk lainnya. (WWF dalam Shibao, 2015).
Faktor-faktor lain yang lebih erat kaitannya dengan keadaan ekonomi Indonesia,
sebagai contoh, banyaknya pohon kelapa sawit berawal dari banyaknya
penggundulan hutan, akibat industri yang menggunakan bahan kayu yang mulai
berkembang pesat pada 1970-an. Pada paruh kedua setelah dekade itu, Indonesia
menjadi pengekspor kayu bulat terbesar di dunia (Welman dalam Shibao, 2015) ,
(The Jakarta Post dalam Shibao, 2015). didorong oleh investasi asing (World
Rainforest Movement dalam Shibao, 2016) dan pembangunan jalan yang
membuka hutan hujan yang sebelumnya tidak dapat diakses. (Welman dalam
Shibao, 2015). Setelah hutan habis, lahan kemuidan ditanami kelapa sawit, yang
menciptakan model bisnis yang sangat menguntungkan. Menjual kayu yang
dipanen dari pembukaan hutan dapat menghasilkan pendapatan hingga $ 10.000
per hektar, menyediakan modal benih untuk mengkonversi lahan menjadi
perkebunan kelapa sawit yang lebih menguntungkan.(Shibao, 2015), meski
kondisi ini mengorbankan kerusakan lingkungan yang parah. Selain itu,
89
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
meningkatnya permintaan minyak nabati telah mengubah cara penanaman kelapa
sawit. Selama dekade terakhir, permintaan global untuk minyak nabati telah
meningkat lebih dari 5 persen per tahun. (Shibao, 2015). Tren ini sebagian
besar didorong oleh masalah kesehatan, yang mencari pengganti lemak hewani,
yang tinggi kolesterol, dengan lemak nabati (Shibao, 2015). Permintaan minyak
kelapa sawit yang meningkat telah menyebabkan kehidupan petani yang semula
subsisten tradisional, dengan menanam berrbagai tanaman dalam sistem
pertanian skala kecil, menjadi satu-satunya tanaman yang tumbuh di dalam
perkebunan besar (WWF dalam Shibao, 2015).
Gambar 3. Perkebunan kelapa sawit dari hutan asli yang ditebangi di Riau,
Indonesia.
Sumber : Butler dalam Shibao, 2015
Dalam pengamatan Shibao (2015), peranan politik sejak 1967 hingga
1998, memberi dampak buruk kepada lingkungan . Diuraikannya, sebagian besar
hutan dihancurkan dan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Persentase
90
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
yang signifikan dari sektor minyak kelapa sawit tetap di bawah kendali kerabat
dan rekan bisnis Soeharto (Aditjondro dalam Shibao, 2/015). Dalam penilaian
Shibao( 2015), saat ini, industri minyak sawit Indonesia terus tumbuh pada tingkat
yang tidak berkelanjutan. Pendapat ini tentu patut mendapat perhatian, agar
minyak kelapa sawit yang telah sukses dalam perdagangan dunia, tidak
mempunyai kesan negatif sebagai hasil pembalakan hutan di mata dunia.
Indonesia sebagai salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa, memang
diharapkan oleh masyarakat dunia untuk menjaga pelestarian hutan. Indonesia
saat ini memiliki 8,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit (Hadinaryanto, 2014
dalam Shibao, 2015) dan sekitar 37 persen di antaranya ditanam pada lahan
gundul.(Butler dalam Shibao, 2015). Pemanfaatan lahan gundul merupakan
langkah lebih baik daripada membiarkan lahan tetap gundul, namun hal yang
lebih baik lagi adalah memelihara lahan kelapa sawit yang sudah ada untuk tidak
mengorbankan lagi hutan yang dilindungi. Manajemen Agribisnis hendaknya
berorientasi kepada pertanian yang berkelanjutan yang memperhatikan pelestarian
lingkungan, tanpa mengabaikan produksi kelapa sawit yang sudah ada, dan
bahkan berupaya untuk meningkatkan produktivitasna.
Total areal kelapa sawit diproyeksikan mencapai 13 juta hektar pada 2020
(Anonymousd, 2017). Jika perencanaan perluasan areal kelapa sawit tidak
bijaksana, maka hutan semakin berisiko mengalami kerusakan. Menurut
Sibhao(2015), salah satu alasan pertumbuhan industri kelapa sawit yang tidak
terkendali adalah ketidakmampuan pemerintah pusat untuk memperluas
jangkauan pengaturannya ke tingkat lokal. Dilanjutkannya, sebagian besar industri
minyak kelapa sawit tetap berada di bawah kendali de facto pejabat lokal,
91
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(Food Tank dalam Shibao, 2015) yang sering berdiri untuk mendapatkan
keuntungan pribadi dari ekspansi perkebunan yang tidak berkelanjutan. Politisi
lokal memberikan izin dan konsesi ilegal untuk perluasan perkebunan kelapa
sawit dan sumber daya alam lainnya dengan imbalan komisi, yang sering
disalurkan kepada kampanye pemilihan umum (Hardinanyanto dalam Shibao,
2015). Jaringan korupsi semacam itu dapat meluas melalui saluran keluarga dan
birokrasi (Shibao, 2015). Pada 2011, Morkes Effendy, yang saat itu menjabat
sebagai bupati Ketapang, ditemukan telah mengeluarkan izin ilegal kepada PT
Kayong Agro Lestari, sebuah perusahaan kelapa sawit yang dimiliki oleh
putranya( Hardinanyanto dalam Shib4ao, 2015). Dilanjutkannya, Pemerintah
Kabupaten Ketapang juga diketahui memiliki saham di Perkebunan Pemuda
Emas, sebuah perusahaan yang terkait dengan perampasan tanah dan perusakan
cadangan hutan ( Friends of Earth dalam Shibao, 2015).
. Pemerintah pusat kekurangan alat-alat dasar yang diperlukan untuk
mengawasi perusahaan kelapa sawit dan salah satu alat tersebut adalah sistem
memantau laju deforestasi yang sedang berlangsung secara akurat (Shibao, 2015).
Sebuah studi terbaru dalam jurnal Nature Climate Change menemukan bahwa
angka-angka pemerintah mungkin telah meremehkan tingkat aktual pembukaan
hutan sebanyak 50 persen, setara dengan 1 juta hektar hutan primer, selama 12
tahun terakhir (Margono dalam Shibao, 2015). Selain itu, perencanaan dan
pemetaan tata guna lahan yang buruk berarti Pemerintah pusat seringkali tidak
jelas mengenai apa tanah yang saat ini digunakan dan untuk tujuan apa.
(Greenpeace dalam Shibao, 2015).
92
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Sementara itu, dalam jangka panjang, permintaan dunia akan minyak sawit
menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan jumlah populasi dunia
yang bertumbuh dan karenanya meningkatkan konsumsi produk-produk dengan
bahan baku minyak sawit seperti produk makanan dan kosmetik. Demikian juga,
pemerintah di berbagai negara sedang mendukung pemakaian biofuel. Hal ini
mendorong Pemerintah memanfaatkan peluang yang baik, melalui para investor.
Hanya beberapa industri di Indonesia yang menunjukkan perkembangan
secepat industri minyak kelapa sawit selama 20 tahun terakhir. Pertumbuhan ini
tampak dalam jumlah produksi dan ekspor dari Indonesia dan juga dari
pertumbuhan luas area perkebunan sawit. Didorong oleh permintaan global yang
terus meningkat dan keuntungan yang juga lebih baik, budidaya kelapa sawit telah
ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para pengusaha
besar di Indonesia (dengan imbas negatif pada lingkungan hidup dan penurunan
jumlah produksi hasil-hasil pertanian lain karena banyak petani beralih ke
budidaya kelapa sawit).
Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor. Negara-
negara tujuan ekspor yang paling penting adalah RRT, India, Pakistan, Malaysia,
dan Belanda. Walaupun angkanya sangat tidak signifikan, Indonesia juga
mengimpor minyak sawit, terutama dari India (Anonymousd, 2017)
Memang mayoritas dari minyak sawit yang diproduksi di Indonesia
diekspor, namun, karena populasi Indonesia terus bertumbuh (disertai kelas
menengah yang berkembang pesat) dan dukungan Pemerintah untuk program
biodiesel, permintaan minyak sawit domestik di Indonesia juga terus berkembang.
Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam negeri sebenarnya bisa berarti
93
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
bahwa pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia akan terhenti di tahun-
tahun mendatang jika pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap
moratorium konversi lahan gambut karena jumlah hutan gambut menurun dengan
dibukanya ke4un kelapa sawit. Adapun perkembangan produksi minyak kelapa
sawit Indonesia sebagai berikut:
Tabel 2. Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia, 2008-2016
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produksi
19.2 19.4 21.8 23.5 26.5 30.0 31.5 32.5 32.0
(juta ton)
Export
15.1 17.1 17.1 17.6 18.2 22.4 21.7 26.4 27.0
(juta ton)
Export
15.6 10.0 16.4 20.2 21.6 20.6 21.1 18.6 18.6
(dollar AS)
Luas Areal
n.a. n.a. n.a. n.a. 9.6 10.5 10.7 11.4 11.8
(juta ha)
Sumber: Indonesian Palm Oil Producers Association (Gapki) & Indonesian
Ministry of Agriculture dalam Anonymousd, 2017.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan Indonesia bisa
memproduksi paling tidak 40 juta ton kelapa sawit per tahun mulai 2020
(Anonymousd, 2017). Target ini hendaknya dapat terlaksana melalui penngkatan
produktivitas lahan dan komoditi, tanpa merusak hutan tropis dan hutan gambut
yang ada. Sebab industri perkebunan dan pengolahan sawit adalah industri kunci
bagi perekonomian Indonesia: ekspor minyak kelapa sawit adalah penghasil
devisa yang penting dan industri ini memberikan kesempatan kerja bagi jutaan
orang Indonesia. Dalam hal pertanian, minyak sawit merupakan industri
terpenting di Indonesia yang menyumbang di antara 1,5 - 2,5 persen terhadap total
produk domestik bruto (PDB). Namun demikian, hendaknya pelaksanaan
mencapai produksi 2020 tidak serta-merta merusak lingkungan.
94
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Hampir 70% perkebunan kelapa sawit terletak di Sumatra, tempat industri
ini dimulai sejak masa kolonial Belanda. Sebagian besar dari sisanya - sekitar
30% - berada di pulau Kalimantan.
Gambar 4. Produksi Kelapa Sawit di Sumatera dan Kalimantan
Sumber : Shibao, 2017
Keterangan :
1. Sumatra
2. Kalimantan
Dalam hal geografi, Riau adalah produsen minyak sawit terbesar di
Indonesia, disusul oleh Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan,
dan Kalimantan Barat.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah total luas area
perkebunan sawit di Indonesia pada saat ini mencapai sekitar 11.9 juta hektar;
hampir tiga kali lipat dari luas area di tahun 2000 waktu sekitar 4 juta hektar lahan
di Indonesia dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Jumlah ini diduga
akan bertambah menjadi 13 juta hektar pada tahun 2020.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran yang sangat
sederhana di sektor kelapa sawit Indonesia karena mereka memiliki perkebunan
yang relatif sedikit, sementara perusahaan-perusahaan swasta besar (misalnya,
Wilmar Group dan Sinar Mas Group) dominan karena menghasilkan sedikit lebih
95
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
dari setengah dari total produksi minyak sawit di Indonesia. Para petani skala
kecil memproduksi sekitar 40 persen dari total produksi Indonesia. Namun
kebanyakan petani kecil ini sangat rentan keadaannya apabila terjadi penurunan
harga minyak kelapa sawit dunia karena mereka tidak dapat menikmati cadangan
uang tunai (atau pinjaman bank) seperti yang dinikmati perusahaan besar.
Gambar 5. Pemilik Kelapa Sawit di Indonesia
Sumber : Shibao, 2017
Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia (contohnya Unilever Indonesia
telah atau sedang melakukan investasi-investasi untuk meningkatkan kapasitas
penyulingan minyak sawit. Hal ini sesuai dengan ambisi Pemerintah Indonesia
untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan dari sumber daya alam dalam
negeri. Indonesia selama ini berfokus (dan tergantung) pada ekspor minyak sawit
mentah (dan bahan baku mentah lainnya) namun selama beberapa tahun terakhir
ini mau mendorong proses pengolahan produk sumber daya alam supaya memiliki
harga jual yang lebih tinggi (dan yang berfungsi sebagai penyangga saat
meluncurnya harga minyak sawit. Kapasitas penyulingan di Indonesia melompat
menjadi 45 juta ton per tahun pada awal 2015, naik dari 30,7 juta ton pada tahun
2013, dan lebih dari dua kali lipat kapasitas di tahun 2012 yaitu 21,3 juta ton.
6.1.1 Kebijakan Pajak Ekspor Minyak Sawit Indonesia
Untuk meningkatkan perkembangan di industri hilir sektor kelapa sawit, pajak
ekspor untuk produk minyak sawit yang telah disuling telah dipotong dalam
96
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, pajak ekspor minyak sawit mentah
(CPO) berada di antara 0%-22,5% tergantung pada harga minyak sawit
internasional. Indonesia memiliki 'mekanisme otomatis' sehingga ketika harga
CPO acuan Pemerintah (berdasarkan harga CPO lokal dan internasional) jatuh di
bawah 750 dollar Amerika Serikat (AS) per metrik ton, pajak ekspor dipotong
menjadi 0%. Ini terjadi di antara Oktober 2014 dan Mei 2016 waktu harga acuan
ini jatuh di bawah 750 dollar AS per metrik ton.
Masalahnya, bebas pajak ekspor berarti Pemerintah kehilangan sebagian
besar pendapatan pajak ekspor (yang sangat dibutuhkan) dari industri minyak
sawit. Oleh karenanya Pemerintah memutuskan untuk mengintroduksi pungutan
ekspor minyak sawit di pertengahan 2015. Pungutan sebesar 50 dollar Amerika
Serikat (AS) per metrik ton diterapkan untuk ekspor minyak sawit mentah dan
pungutan senilai 30 dollar AS per metrik ton ditetapkan untuk ekspor produk-
produk minyak sawit olahan. Pendapatan dari pungutan baru ini digunakan
(sebagian) untuk mendanai program subsidi biodiesel Pemerintah.
Lima faktor yang mempengaruhi harga minyak kelapa sawit :
(1) permintaan dan persediaan.
(2) harga minyak nabati lain (terutama kedelai)
(3) cuaca
(4) kebijakan impor negara-negara yang mengimpor minyak kelapa sawit
(5) perubahan dalam kebijakan pajak dan pungutan ekspor/impor
Pada Februari 2015, Pemerintah mengumumkan kenaikan subsidi biofuel
dari Rp 1.500 per liter menjadi Rp 4.000 per liter, sebuah upaya untuk melindungi
para produsen biofuel domestik. Melalui program biodiesel ini, Pemerintah
97
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
mengkompensasi para produsen karena perbedaan harga antara diesel biasa dan
biodiesel yang terjadi akibat rendahnya harga minyak mentah dunia (sejak
pertengahan 2014). Selain untuk mendanai subsidi ini, hasil dari pungutan ekspor
juga disalurkan untuk penanaman kembali, penelitian, dan pengembangan
sumberdaya manusia di industri minyak sawit Indonesia.
6.1.2 Isu-Isu Lingkungan Hidup Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah sering dikritik kelompok-kelompok pencinta
lingkungan hidup karena terlalu banyak memberikan ruang untuk perkebunan
kelapa sawit (yang berdampak pada penggundulan hutan dan penghancuran lahan
bakau). Oleh karenanya, sejalan dengan semakin banyaknya perusahaan
internasional yang mencari minyak sawit ramah lingkungan sesuai dengan kriteria
Roundtable on Sustainable Palm Oil - perkebunan-perkebunan di Indonesia dan
Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan. Uni
Eropa telah membuat aturan-aturan hukum yang lebih ketat mengenai produk-
produk impor yang mengandung minyak sawit, dan hal ini merupakan suatu
tantangan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa adanya perkebunan minyak
kelapa sawit Indonesia tidaklah seburuk yang diduga.
Pada tahun 2011, Indonesia medirikan Indonesian Sustainable Palm Oil
(ISPO) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing global dari minyak sawit
Indonesia dan mengaturnya dalam aturan-aturan ramah lingkungan yang lebih
ketat. Semua produsen minyak sawit di Indonesia didorong untuk mendapatkan
sertifikasi ISPO. Namun, ISPO ini tidak diakui secara internasional.
98
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
6.1.3. Moratorium Mengenai Konsesi Baru Hutan Perawan
Pemerintah Indonesia menandatangani moratorium berjangka waktu dua
tahun mengenai hutan primer yang mulai berlaku 20 Mei 2011 dan selesai masa
berlakunya pada Mei 2013. Setelah habis masa berlakunya, Presiden Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono memperpanjang moratorium ke dua tahun
selanjutnya. Moratorium ini mengimplikasikan pemberhentian sementara dari
pemberian izin-izin baru untuk menggunakan area hutan hujan tropis dan lahan
bakau di Indonesia. Sebagai gantinya Indonesia menerima paket 1 milyar dollar
AS dari Norwegia. Pada beberapa kesempatan, media internasional melaporkan
bahwa moratorium ini telah dilanggar oleh perusahaan-perusahaan Indonesia.
Kendati begitu, moratorium ini berhasil membatasi - untuk sementara - ekspansi
perkebunan-perkebunan sawit. Pihak-pihak yang skeptis terhadap moratorium
tersebut menunjukkan bahwa sebelum penerapannya Pemerintah Indonesia telah
memberikan konsesi tanah seluas 9 juta hektar untuk lahan baru. Selain itu,
perusahaan-perusahaan besar minyak sawit masih memiliki lahan luas yang baru
setengahnya ditanami, berarti masih banyak ruang untuk ekspansi. Pada Mei
2015, Presiden Joko Widodo kembali memperpanjang moratorium ini untuk
periode 2 tahun.
6.1.4. Prospek Masa Depan Industri Minyak Sawit di Indonesia
Harga minyak sawit naik tajam setelah tahun 2005 namun krisis global
menyebabkan penurunan tajam harga CPO di tahun 2008. Terjadi rebound yang
kuat namun setelah tahun 2011 yang menyebabkan harga CPO melemah, terutama
karena permintaan dari China telah menurun, sementara rendahnya harga minyak
mentah (sejak pertengahan 2014) mengurangi permintaan biofuel berbahan baku
99
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
minyak sawit. Karena itu, prospek industri minyak sawit suram dalam jangka
waktu pendek, terutama karena Indonesia masih terlalu bergantung pada CPO
dibandingkan produk-produk minyak sawit olahan.
Pada saat permintaan global kuat, bisnis minyak sawit di Indonesia
menguntungkan karena alasan-alasan berikut:
• Margin laba yang besar, sementara komoditi ini mudah diproduksi
• Permintaan internasional yang besar dan terus berkembang seiring kenaikan
jumlah penduduk global.
• Biaya produksi minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia merupakan biaya
produksi minyak nabati paling murah di dunia.
• Tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan produk minyak nabati lain,
misalnya minyak kedele, minyak kapas, minyak bunga matahari, dsb.
• Penggunaan biofuel diduga akan meningkat secara signifikan, sementara
penggunaan minyak mentah akan berkurang
Masalah-masalah yang menghalangi perkembangan industri minyak sawit dunia:
• Kesadaran bahwa penting untuk membuat lebih banyak kebijakan ramah
lingkungan
• Konflik masalah tanah dengan penduduk lokal karena ketidakjelasan
kepemilikan tanah
• Ketidakjelasan hukum dan perundang-undangan
• Biaya logistik yang tinggi karena kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur.
6.2 Masalah yang dihadapi oleh Agribisnis Indonesia
(1) Swasembada pangan yang belum tercapai
100
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Pemerintah Indonesia telah menempatkan swasembada beberapa produk pangan
prioritas utama. Hal ini terutama dikarenakan Indonesia memiliki konsumsi beras
per kapita tertinggi di dunia (sekitar 139 kilo per kapita per tahun). Namun,
hingga kini, Indonesia masih bergantung pada impor dari Vietnam dan Thailand
untuk mengamankan pasokan beras domestik. Tanaman pangan lain yang menjadi
target program swasembada adalah kacang kedelai, jagung, dan gula. Program
swasembada pangan hingga saat ini belum ada yang tercapai. Jikalau dikatakan
tercapai, maka kondisi itu hanya bersifat sementara, misalnya 1-2 tahun , untuk
kemudian terjadi impor kembali. Sejak 2007 pemerintah telah memulai program
revitalisasi petani kecil untuk meningkatkan produksi, namun hingga saat ini
belum membawa hasil yang signifikan.
(2) Nilai Tambah Produk Lain yang Belum Tercapai
Dalam jangka panjang, pengembangan usaha pertanian difokuskan kepada
produk-produk hasil olahan yang dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian
nasional, termasuk pengembangan agroindustri. Baru kelapa sawit yang telah
membawa nilai tambah, sementara produk lain yang berpotensia yang dapat
dikembangkan seperti kelapa sawit adalah coklat, kopi dll, masih belum dikelola
dengan perolehan nilai tambah sebaik kelapa sawit.
(3) Nilai PDB sektor pertanian masih cukup berpotensi
Meski sumbangan PDB sektor pertanian belum sebesar sektor industri, namun
sektor pertanian masih berpotensi dalam menyumbang PDB secara nasional,
yang tentunya juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat \di
Indonesia, terutama petani.., Peranan penting agribisnis (dalam bentuk sumbangan
pada industri non-migas dan ekspor non-migas), dinilai cukup tinggi. Sementara
101
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
itu, hal yang mendukung potensinya sektor pertanian adalah karena pangsa impor
agribisnis relatif rendah, yang artinya sektor agribisnis dari sisi ekonomi dan
neraca ekonomi kurang membebani neraca perdagangan dan pembayaran luar
negeri.
(4) Belum Terjadi Perbaikan Kualitas yang Signifikan
Jika terjadi peningkatan produktivitas pada hasil produk pertanian, belum diikuti
oleh perbaikan koalitas, dan oleh karenanya, diperlukan perbaikan teknologi
(5) kualitas tenaga kerja di sektor pertanian, masih perlu ditingkatkan
(6) masalah kemiskinan yang masih melanda petani Indonesia
(7) rendahnya produktivitas komoditi pertanian Indonesia
(8) masih lemahya posisi tawar petani,
(9) ketidakadaannya kelembagaan yang kokoh mendukung usaha petani
(10) masih kurangnya atau lemahnya sistem pasar komoditi produk pertanian,
(11) kurang terserapnya hasil komodit dengan baik akibat infrastruktur yang
masih kurang memadai.
(12) struktur agribisnis, untuk hampir semua komoditi, hingga saat ini masih
lemah karena berdiri sendiri-sendiri tanpa dukungan yang kokoh dari Pemerintah.
(13)Pemilikan Lahan Sempit
(14) Mutu SDM Rendah
(15) Penerapan IPTEK belum maksimal
(16) Agribisnis Belum Sepenuhnya Berkembang
(17) Permodalan Minim
(18)Daya Saing Produk Lemah
(19) Infrastruktur belum Mendukung
102
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(20) Penggunaan lahan yang belum maksimal
Pada tahun 1999 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian mencapai 47
juta hektar, sedangkan luas lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian sebesar
17,8 juta hektar . Sedangkan menurut data BPS tahun 2001, luas lahan yang
digunakan untuk pertanian maupun luas lahan sementara yang tidak diusahakan
meningkat menjadi 64,8 juta hektar. Luas lahan tersebut belum termasuk luas
lahan yang ada di propinsi Maluku dan Irian Jaya. Dari data statistik tahun 1999,
bila dirinci, penggunaan lahan yang paling luas adalah untuk perkebunan yaitu
sebesar 16,5 juta hektar (25,54%). Urutan terbesar selanjutnya adalah lahan yang
digunakan untuk tegal atau kebun sebesar 12,8 juta hektar atau 19,71 %,
kemudian lahan untuk tanaman kayu-kayuan dan sawah masing-masing sekitar
8,9 juta hektar dan 8,1 juta hektar (13,75% dan 12,51%). Selain itu, lahan yang
sementara tidak diusahakan mencapai 10,3 juta hektar atau 15,84 %, sedangkan
untuk bangunan dan halaman mencapai 5,1 juta hektar (7,92%). Penggunaan
untuk padang rumput dan tambak, masing-masing sebesar 2,4 juta hektar (3,74%)
dan 0,5 juta hektar (0,70%).
Gambar 6. Persentase Penggunaan Lahan di Indonesia, 1999
Sumber : Hindarti, 2019
103
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(21) Perkebunan yang belum Maksimal
Komoditi perkebunan di Indonesia sangat beragam, mulai aren, kelapa, teh, kopi,
kakao hingga tembakau. Sektor perkebunan dikelola baik oleh masyarakat,
pemerintah ataupun pihak swasta. Perkembangan luas area perkebunan di
Indonesia juga berfluktuasi.
Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada komoditi kakao dan kelapa
sawit. Luas area untuk komoditi kakao terus meningkat dari 749.917 hektare
(tahun 2000) menjadi 1.191.742 di tahun 2006. Sama halnya dengan kelapa sawit,
luas lahan meningkat dari 4.158.079 hektare (tahun 2000) menjadi 6.074.926
hektare (2006). Peningkatan luas area ini berkaitan dengan kebijakan Revitalisasi
pertanian yang dicanangkan pemerintah, masih diperlukan upaya penanganan
yang lebih maksimal.
(22) Perikanan Belum Sepenuhnya Tertangani
Sebagai salah satu negara bahari, Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar
dalam sub sektor perikanan. Berdasarkan neraca perdagangan tahun 2000-2006,
ekspor produk perikanan masih mengalami surplus dengan peningkatan sebesar
9% di tahun 2006 dibandingkan tahun 2005. Besarnya nilai peningkatan tersebut
mencapai US$ 2 juta. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDB Nasional
juga menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2001-2005 dengan kenaikan
rata-rata sebesar 12,77%.
Pihak Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menyatakan bahwa selama
periode Januari-Agustus 2006 ekspor perikanan budidaya mencapai 664,5 juta ton
dengan nilai ekspor sebesar US$ 1,4 milliar, hingga akhir tahun 2006 diperkirakan
total ekspor mencapai US$ 2,1 milliar.Berdasarkan data dari Departemen
104
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Kelautan dan Perikanan (DKP), komoditas ekspor perikanan budidaya yang
menjadi unggulan tahun 2006 yaitu udang dengan volume ekspornya mencapai
112.5 juta ton dan nilai ekspor sebesar US$ 739,20 juta, dilanjutkan tuna dengan
volume 58.633 ton (US$ 168,72 juta) dan rumput laut kering sebesar 57.683 (US$
28,55 juta). Pangsa pasar ekspor produk perikanan Indonesia juga telah merambah
berbagai negara seperti Asia (Jepang, China), Uni Eropa dan Amerika. Amerika
merupakan tujuan utama Indonesia dengan volume ekspor tahun 2006 mencapai
83.347 ton, diikuti China sebanyak 78.686 ton, kemudian Jepang dan Uni Eropa
masing-masing 74.973 ton dan 51.976 ton (Departemen Kelautan dan Perikanan,
2018).
(23) Kehutanan Belum Maksimal
Indonesia merupakan salah satu negara paru-paru dunia karena area
hutannya yang cukup besar. Hutan di Indonesia terbagi dalam kategori hutan
produksi, hutan untuk wisata dan suaka serta hutan lindung. Pemanfaatan hutan
untuk produksi mencapai 81,9 juta hektar dengan 3 kategori yaitu hutan produksi
terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi.
Komoditi kehutanan yang paling besar yaitu kayu selain komoditas non kayu.
(24) Peternakan yang Belum Maksimal
Komoditi pertenakan yang berpotensi dinaikkan ekspornya meliputi kulit
samak, susu, ternak babi, daging ayam, pakan ternak dan daging babi. Komoditi
yang paling besar dijual di pasar luar negeri yaitu kulit samak dengan volume
ekspor mencapai 8.128.481 kg (tahun 2003) dengan nilai mencapai US$ 65 juta.
Beberapa negara tujuan untuk komoditi peternakan Indonesia yaitu Hongkong,
Brasil, Italia, Vietnam dan Spanyol.
105
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
(25) Beberapa produk impor buah masih tinggi
(26) Petani tersisihkan oleh perhatian Pemerintah
(27) organisasi petani kurang berfungsi,
(28) Beberapa infrastruktur yang dibutuhkan terabaikan,
(29) Ketersediaan investasi rendah,
(30) akses kepada pasar masih terlalu lemah,
(31) rendahnya teknologi yang digunakan,
(32) akses lembaga keuangan relatif lemah
6.3 Pertanian/Agribisnis di Negara Maju
Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, telah berhasil
mengembangkan sektor pertanian dengan kokoh. Negara-negara maju, sejak lama
sudah melihat bagaimana potensi pertanian dalam perekonomian mereka.
Keunggulan daya saing ditentukan oleh kemampuan mendayagunakan
keunggulan komparatif yang dimiliki mulai dari hulu sampai hilir, dalam
menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Artinya,
pendayagunaan keunggulan sisi penawaran ditujukan untuk memenuhi keinginan
konsumen. Kemampuan untuk menyediakan produk yang berkembang, sangat
menentukan keunggulan bersaing di pasar internasional. Negara-negara yang
berbasis agribisnis, seperti Australia dan Selandia Baru, mampu bersaing di pasar
internasional disebabkan kemampuan negara-negara tersebut dalam menjual apa
yang diinginkan konsumen. . Negara-negara yang berbasis pertanian yang
kemudian belum berhasil membangun sektor pertanian, menjadi negara-negara
yang belum sepenuhnya maju. Contoh dari negara-negara ini adalah negara-
negara di kawasan Afrika.
106
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Bagi sebuah negara agraris seperti Indonesia, sektor agribisnis atau
pertanian (meliputi perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan serta
tanaman holtikultural) mempunyai peranan yang cukup vital. Artinya, peran
pertanian dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi baik secara
langsung maupun tidak langsung, cukup signifikan, seperti: menyerap tenaga
kerja, sumber pendapatan bagi masyarakat, menyediakan bahan pangan dan bahan
baku serta mendatangkan devisa bagi negara.
Pentingnya peranan sektor pertanian juga terlihat dalam hal penyerapan
tenaga kerja, sekitar 42% dari total tenaga kerja di Indonesia terserap di sektor
pertanian ini atau mencapai 40,1 juta orang. Pertumbuhan sektor pertanian ini
juga membawa dampak terhadap tingkat kehidupan para petaninya. Pada bulan
Desember 2006, nilai tukar petani mengalami peningkatan sebesar 106,4 atau naik
sebesar 7,6% jika dibandingkan akhir 2005.
6.4. Solusi dalam Pengembangan Agribisnis Indonesia
Solusi utama dalam agribisnis Indonesia adalah ketersedianya dana yang
dibutuhkan bagi pengembangan agribisnis. Adapun dana yang dibutuhkan, akan
diperuntukkan kepada :
(1) Penyediaan Sarana dan prasarana pertanian
(2) Pengembangan SDM
(3) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi
(4) Perbaikan bagi Kelembagaan yang Kokoh
(5) Penyediaan Informasi Pertanian.
(6) Meningkatkan Mutu / Kualitas Produk Pertanian
(7) Perbaikan Efisiensi Produksi
107
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
( 8) Meningkatkan Nilai Tambah
(9) Memberikan Subsidi bagi Kebutuhan Hidup Petani
(10) Meningkatkan Pemasaran Hasil Pertanian
(11) Turut Terlibat dalam Resiko Usaha Petani
a. Kualitas SDM
Faktor sumber daya manusia dalam sektor pertanian ini bukan hanya
petani saja, namun juga semua pihak yang berkepentingan dalam pertanian seperti
buruh tani, pengepul, pedagang, pengusaha, serta pemerintah. Petani merupakan
salah satu SDM yang berperan penting dalam pengembangan pertanian dan
tingkat SDM di sektor pertanian menjadi kunci kekuatan sektor ini. Tingkat
perkembangan sektor pertanian sering kali dikaitkan dengan kualitas petani.
Tingkat pendidikan dan kemampuan petani di Indonesia memang bisa dikatakan
masih cukup rendah, namun tentu saja petani tidak bisa disalahkan terus menerus
dengan kondisinya tersebut. Pemerintah pun melakukan upaya untuk
meningkatkan kualitas petani salah satunya dengan penyuluhan pertanian.
b. Akses Teknologi Informasi
Faktor ini merupakan faktor yang erat hubungannya dengan kualitas SDM.
Saat ini, akses informasi serta akses teknologi pertanian masih sangat sulit bagi
sebagian besar petani. Sebagian besar petani tinggal di daerah dengan akses
informasi dan teknologi yang cukup sulit. Program penyuluhan yang diterapkan
oleh pemerintah kepada petani terutama di daerah yang terpencil dengan tujuan
untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ternyata belum juga
memberikan perubahan yang signifikan. Akses informasi yang mudah akan
memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kualitas petani yang
108
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
berpengaruh pula pada peningkaan kualitas produk. Informasi juga tidak hanya
pada upaya peningkatan kualitas namun dengan informasi, petani dapat
mengetahui perkembangan pasar, permintaan pasar sehingga dapat melakukan
penyesuaian.
c. Pasar dan Modal
Modal dan akses pasar juga merupakan masalah penting yang
menghambat perkembangan sektor pertanian terutama para smallholders
(produsen kecil). Potensi sektor pertanian sebenarnya cukup besar namun banyak
petani yang terhambat oleh pasar. Terhambatnya pasar juga berkaitan dengan
kualitas produk pertanian yang dihasilkan di Indonesia.
d. Kualitas Produk
Kualitas produk pertanian yang tidak sesuai dengan permintaan pasar juga
menjadi faktor penghambat perkembangan sektor ini. Dalam hal kualitas,
memang produk Indonesia masih banyak yang mempunyai kualitas di bawah
standar. Kasus embargo seringkali dilakukan oleh negara yang mengimpor produk
itu dari Indonesia. Seperti kasus embargo China atas produk perikanan Indonesia
baru baru ini. Pemerintah China awal Agustus yang lalu mengeluarkan keputusan
untuk melakukan embargo makanan hasil laut dari Indonesia karena produk
perikanan indonesia dinilai tidak aman dan mengandung logam berat dan bakteri
patogen.
Kasus lain yang juga diakibatkan buruknya kualitas produk pertanian
Indonesia yaitu kasus penolakan 28 ton udang asal Sumatera Utara sekitar bulan
April yang lalu. Sebanyak 4 kontainer ukuran 20 feet yang berisi udang dari
Sumatera Utara ditolak negara Jepang. Penolakan tersebut diakibatkan kandungan
109
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
antibiotik yang terkandung dalam udang tersebut mencapai 0,01 ppm (part per
million). Banyak kasus serupa yang menimpa sektor pertanian kita dan itu cukup
memberikan gambaran bahwa kualitas produk pertanian Indonesia masih buruk.
e. Faktor Lain
Masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap perkembangan sektor
pertanian di Indonesia, seperti belum kondusifnya iklim investasi di Indonesia
(berkaitan dengan kebijakan pemerintah), organisasi kelembagaan yang masih
lemah, banyaknya kasus illegal fishing (perikanan), illegal logging, serta adanya
infrastruktur yang masih buruk.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan
perkembangan sektor agribisnis yaitu dengan revitalisasi revitalisasi pertanian,
perikanan dan kehutanan.
a. Revitalisasi Pertanian
Dalam program revitalisasi pertanian, dilakukan upaya untuk memecahkan
persoalan yang dihadapi dalam sektor pertanian seperti rendahnya
produktivitas dan kualitas produk dari peternakan, perkebunan dan
holtikultura serta infrastruktur yang ada. Hingga pertengahan tahun 2007,
revitalisasi pertanian telah menerapkan 5 langkah yang disebut Pancayasa.
Pancayasa terdiri dari: Pertama, Pembangunan perbaikan infrastruktur
pertanian termasuk infrastruktur untuk pembenihan, riset. Kedua, Penguatan
kelembagaan petani melalui penguatan kelompok tani. Ketiga, Perbaikan
110
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
penyuluhan dengan membenahi lembaga penyuluh dan tenaga penyuluh.
Keempat, Perbaikan pembiayaan yang mempermudah akses petani terhadap
modal. Terakhir yang Kelima, Sistem pasar yang menguntungkan petani dan
peternak.
b. Revitalisasi Perikanan
Untuk meningkatkan produksi di sektor perikanan pada tahun 2006 hingga
pertengahan 2007, melalui revitalisasi perikanan pemerintah telah melakukan
perbaikan infrastruktur. Perbaikan itu seperti pembangunan dan rehabilitasi
saluran tambak seluas 7,6 ribu ha, pengembangan sarana budidaya tambak
menjadi seluas 47,8 ribu ha serta pembangunan beberapa sarana usaha
perikanan seperti unit pembenihan rakyat dan unit pelabuhan perikanan.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga melakukan peneilitian di
sektor kelautan dan perikanan.
c. Revitalisasi Kehutanan
Kebijakan revitalisasi kehutanan dititikberatkan pada upaya menggiatkan
industri kehutanan melalui pembangunan hutan tanaman industri dan
peningkatan hasil hutan non kayu. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu:
Pertama, Revitalisasi industri kehutanan. Kedua, Pemberdayaan masyarakat
di dalam dan di sekitar hutan, Ketiga Rehabilitasi dan pemulihan cadangan
sumber daya alam dan yang Keempat Perlindungan dan konservasi sumber
daya alam.
Komoditi sektor agribisnis berperan penting dalam menjaga ketahanan
pangan di Indonesia. Dengan kondisi sektor agribisnis yang potensial dan
111
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
dengan pengembangan yang kontinyu, Indonesia bisa menghadapi kejadian
krisis pangan yang semakin parah di kemudian hari.
Tiga Langkah untuk Naikkan Daya Saing Produk Pertanian
Dalam Workshop Program Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi
(P4MI) yang telah dilaksanakan di Hotel Sahid Jaya Solo, pada tanggal 13–16
Juli 2009 dengan topik “Pengembangan Inisiatif Lokal dan Kapasitas Institusi
Lokal” yang diikuti oleh pelaksana kegiatan di daerah (BPTP dan PIU ) serta
pelaksana kegiatan di pusat (PCMU, PUSDATIN, LSM, dan konsultan)
disebutkan ada tiga langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya
saing produk pertanian yakni:
1.Memperbesar akses petani ke pasar modern melalui penguatan struktur rantai
pasok; 2.Memodernisir pasar tradisional;
3.Peningkatan ekspor.
Hal itu terungkap dalam Workshop Nasional: ”Peningkatan Nilai Tambah dan
Daya Saing Produk Pertanian” di Jakarta. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian Departemen Pertanian Prof. Zaenal Bachrudin mengatakan agar tiga
langkah besar itu bisa dijalankan perlu ada sinkronisasi kebijakan pengembangan
komoditas unggulan daerah di Departemen Pertanian dengan kebijakan
pengembangan Agro-Based Industry di Departemen lainnya, seperti Departemen
Perdagangan dan Departemen Perindustrian.
Diungkapkannya banyak komoditas yang menjadi prioritas di Departemen
Pertanian namun tidak masuk dalam definisi komoditi utama dan komoditi
potensial di Departemen Perdagangan. “Maka itu perlu upaya menyinergikan
112
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
pelaksanaan kebijakan antar departemen agar dapat mengangkat harkat dan
derajat petani,” tambahnya.
Ada 10 komoditas utama dan 10 komoditas potensial di Departemen
Perdagangan. Dari 10 komoditas utama tersebut empat di antaranya komoditi
pertanian yakni: Kapi, Kakao, Minyak Kelapa Sawit, Karet dan Produk Karet.
Dan dari 10 komoditas potensial tiga komoditas di antaranya terkait dengan
pertanian yakni: rempah-rempah (lada, jahe dll), obat-obatan herbal dan makanan
olahan (buah, sayuran dll).
Kebijakan stabilisasi harga pun perlu disinkronisasi. Kebijakan stabilisasi harga di
Departemen Perdagangan adalah untuk melindungi konsumen yakni agar harga
terjangkau oleh masyarakat. Seperti yang dilakukan untuk beras dan gula.
Namun ada mekanisme kebijakan lain yang lebih bisa menolong petani, seperti
pasar lelang dan resi gudang. Kebijakan itu ditujukan untuk menolong petani
dalam mendapatkan uang tunai sebelum produknya laku dijual.Selain itu, Zaenal
menambahkan kebijakan pembinaan pengembangan agroindustri masih terkotak-
kotak. “Deptan punya peran yang sangat kecil dalam bidang itu,” tambahnya.
Deptan menginginkan agar PP 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pembinaan
Agroindustri direvisi (diperbaharui).
2.5. Peranan Good Agricultural Practices Dalam Agribisnis Indonesia
Saat ini kita telah memasuki era globalisasi ekonomi yang memaksa petani
sebagai produsen utama produk-produk pertanian secara langsung dan tidak
langsung memasuki persaingan dengan banyak produsen lain ditingkat global.
Produk-produk pertanian tidak hanya bersaing dengan produk-produk pertanian
luar negeri di pasar global tetapi juga di pasar domestik. Dalam pasar global
113
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
terbuka suatu negara tidak boleh mengenakan proteksi dan hambatan tarif
terhadap komoditi yang masuk kewilayahnya. Dalam kondisi demikian
persaingan menjadi semakin sengit dan ketat, produsen kuat bersaing dengan
produsen lemah, akibatnya produsen yang kalah bersaing akan semakin
termarginalkan. Keadaan demikian yang sekarang sedang terjadi dengan produk-
produk pertanian khususnya produk pangan buah-buahan dan sayuran. Indonesia.
Sedangkan dunia pertanian abad ini sendiri juga menghadapi tiga macam
tantangan utama. Organisasi Pangan dunia yang bernaung di bawah PBB (FAO)
dalam pertemuan pangan dunia menyatakan tiga tantangan utama pertanian saat
ini yakni ; 1) peningkatan ketahanan pangan, mata pencaharian dan pendapatan
penduduk pedesaan, 2) memenuhi peningkatan kebutuhan akan berbagai macam
produk pangan yang aman, 3) pelestarian sumber daya alam dan lingkungan
(FAO, 2003).
Melihat perkembangan tersebut maka diperlukan sebuah langkah yang
bersifat strategis agar dunia pertanian terutama di Indonesia dapat menjawab tiga
tantangan tersebut. Pemerintah sebenarnya telah menyadari hal tersebut, sehingga
pada awal masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono munculah
sebuah program revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Secara
nasional, fokus pengembangan produk dan bisnis PPK mencakup lingkup kategori
produk yang berfungsi dalam hal :
a. Membangun ketahanan pangan, yang terkait dengan aspek pasokan produk,
aspek pendapatan dan keterjangkauan, dan aspek kemandirian.
b. Sumber perolehan devisa, terutama yang terkait dengan keunggulan
komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar internasional.
114
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
c. enciptaan lapangan usaha dan pertumbuhan baru, terutama yang terkait
dengan peluang pengembangan kegiatan usaha baru dan pemanfaatan pasar
domestik.
d. Pengembangan produk-produk baru yang terkait dengan berbagai isu global
dan kecenderungan pasar global.
Kebijakan dan strategi umum yang diambil dalam pelaksanaan RPPK sendiri
adalah pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing dan pelestarian dan
pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam berkelanjutan. Peningkatan
daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kemandirian dilakukan antara lain
dengan praktek usaha pertanian yang baik (Good Agricultural Practices = GAP).
Permasalahan Pangan dan Penerapan GAP
Dewasa ini di tingkat global telah terjadi perubahan nilai dan konsep pada
konsumen terhadap produk-produk pertanian yang mereka konsumsikan. Hal ini
mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku dan sikap mereka dalam membeli
suatu produk agrisbisnis. Meningkatnya kesadaran konsumen akan kaitan
kesehatan dan kebugaran dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan
konsumen akan nutrisi produk-produk yang sehat, aman dan menunjang
kebugaran. Keamanan pangan menjadi kunci yang menentukan kualitas produk
pangan.
Deininger (2006) menyatakan kelemahan dalam penanganan sistem keamanan
pangan dapat menyebabkan biaya yang tinggi bagi masyarakat dan berakibat bagi
ekonomi global. World Health Organization (WHO) memperkirakan kurang lebih
2,2 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit diare yang disebabkan oleh
bakteri, virus, dan organisme patogen yang disebarkan oleh air yang telah
115
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
terkontaminasi. Di India diperkirakan 20 persen kematian dari balita disebabkan
oleh penyakit diare. Saat wabah SARS menyebar di Asia Timur tahun 2003
ternyata menyebabkan hilangnya pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen dari
wilayah tersebut pada seperempat tahun pertama, walaupun hanya 800 orang yang
akhirnya meninggal akibat penyakit tersebut.
Sedangkan Lowy Institut for International Policy (2006) memperkirakan
mewabahnya penyakit avian invluenza menyebabkan meningkatnya biaya
ekonomi bagi 1,4 juta penduduk dunia yang mendekati 0,8 persen GDP dunia atau
sekitar US$ 330 miliar. Sedangkan di lain pihak timbulnya peningkatan reaksi di
berbagai negara untuk melindungi negaranya dari ancaman kemanan pangan dapat
menyebabkan konsekuensi negatif bagi negara pengekspor pangan. Diperkirakan
akibat dari pemberlakuan penyelarasan nilai standar aflatoksin bagi 15 negara
Eropa oleh Uni Eropa dari bahan makanan impor 9 negara Afrika telah
menyebabkan berkurangnya ekspor negara Afrika sebanyak 64 persen atau senilai
US$ 670 juta.
Meningkatnya kesadaran konsumen akan produk pertanian yang aman bagi
kesehatan dan kebugaran, aman bagi keselamatan dan kesehatan kerja, aman bagi
kualitas dan kelestarian lingkungan hidup mendorong dikembangkannya berbagai
persyaratan teknis bahwa produk harus dihasilkan dengan teknologi yang akrab
lingkungan. Penilaian terhadap aspek keselamatan kerja, kesehatan konsumen dan
kualitas Lingkungan dilakukan pada keseluruhan proses agribisnis dari hulu
sampai hilir (pemasaran). Konsumen hijau mendesak WTO agar perubahan sikap
perilaku dan permintaan akan kualitas produk-produk pertanian diintegrasikan
dalam kebijakan perdagangan internasional produk-produk pertanian. Permintaan
116
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
dan desakan konsumen kemudian ditampung dan diperhatikan oleh organisasi
perdagangan dunia (WTO). Hal tersebut di ataslah yang juga turut mendorong
berbagai negara di belahan dunia untuk menerapkan Praktek Pertanian yang baik
atau Good Agricultural Practices (GAP)
Meskipun secara umum implikasi dari perdagangan bebas ternyata belum
sepenuhnya dapat diterapkan untuk Indonesia. Hal ini dapat ditegaskan oleh
Achterbosch (2004) yang menyatakan bahwa meskipun rezim perdagangan di
Indonesia yang cukup bebas telah lama diberlakukan semenjak menghadapi krisis
Asia akhir tahun 1990, diperkirakan hanya sedikit masyarakat pertanian dengan
skala kesejahteraan kecil menengah yang mendapat efek langsung dari
perdagangan bebas. Hal ini disebabkan masih minimnya integrasi pertanian di
Indonesia dengan perdagangan bebas.
Sementara itu, kondisi dunia pertanian di Indonesia sendiri juga mengalami
tantangan yang cukup merisaukan, salah satunya adalah terjadinya konversi lahan
yang cukup besar. Mariyono et all (2007) menyatakan konversi lahan pertanian
mengakibatkan dua dampak yang sangat tidak menguntungkan baik secara
ekonomi maupun ekologi. Secara ekologi konversi lahan akan menyebabkan
menurunnya daya dukung lahan. Konversi lahan pertanian juga secara potensial
dapat menyebabkan berkurangnya produksi air tanah dan menyebabkan banjir.
Sedangkan secara ekonomi konversi lahan tidak hanya berimbas pada
berkurangnya lahan dan produksi pertanian, tetapi juga menyebabkan
berkurangnya kesempatan kerja baik bagi buruh tani maupun pemilik lahan,
berkurangnya investasi infrastruktur di bidang pertanian, seperti irigasi,
kelembagaan, dan menyebabkan konsekuensi negatif bagi lingkungan.
117
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Secara umum konversi lahan pertanian dalam jangka panjang akan
menurunkan kesejahteraan petani, yang dapat diidentifikasikan dari penurunan
luas lahan milik dan luas lahan garapan, penurunan pendapatan pertanian, serta
tidak signifikannya pendapatan non pertanian (Ruswandi, et all, 2007).
Besarnya tuntutan akan produk pangan yang baik, sehat dan berwawasan
lingkungan adalah suatu hal yang tidak dapat terelakkan. Peningkatan tingkat
pendidikan dan ekonomi masayrakat mengekibatkan tuntutan baru akan pangan di
berbagai belahan dunia. Kondisi tersebut mau tidak mau harus dihadapi oleh
Indonesia. Tuntutan akan produk pangan yang aman tidak hanya dipandang
sebagai hambatan bagi dunia pertanian di Indonesia, namun juga harus dilihat
sebagai sebuah tantangan dan peluang bagi para stakeholder di bidang pertanian.
Implementasi Penerapan GAP dalam Agribisnis di Indonesia
Departemen Pertanian (2008) menerangkan bahwa penerapan GAP melalui
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik lokasi, spesifik komoditas dan
spesifik sasaran pasarnya, dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan
kualitas produk yang dihasilkan petani agar memenuhi kebutuhan konsumen dan
memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan produk padanannya dari luar
negeri.
Dasar hukum penerapan GAP di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 61/Permentan/OT.160/11/2006, tanggal 28 November 2006 untuk
komoditi buah, sedangkan untuk komoditas sayuran masih dalam proses
penerbitan menjadi Permentan. Dengan demikian penerapan GAP oleh pelaku
usaha mendapat dukungan legal dari pemerintah pusat maupun daerah.
118
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Maksud dari GAP/SOP adalah untuk menjadi panduan umum dalam
melaksanakan budidaya tanaman buah, sayur, biofarmaka, dan tanaman hias
secara benar dan tepat, sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang
baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek
keamanan, keselamatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang
berkelanjutan.
Tujuan dari penerapan GAP/SOP diantaranya; (1) Meningkatkan produksi dan
produktivitas, (2) Meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi, (3)
Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing, (4) Memperbaiki efisiensi
penggunaan sumberdaya alam, (5) Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian
lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan, (6) Mendorong petani dan
kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap
kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, (7) Meningkatkan peluang
penerimaan oleh pasar internasional, dan (8) Memberi jaminan keamanan
terhadap konsumen. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya
keamanan pangan, jaminan mutu, usaha agribisnis hortikultura berkelanjutan dan
peningkatan daya saing.
Tahapan kegiatan pelaksanaan penerapan GAP/SOP adalah sebagai berikut : (1)
sosialisasi GAP, (2) penyusunan dan perbanyakan SOP budidaya, (3) penerapan
GAP/SOP budidaya, (4) identifikasi kebun/lahan usaha, (5) penilaian kebun/lahan
usaha, (6) kebun/lahan usaha tercatat/teregister, (7) penghargaan kebun/lahan
usaha GAP kategori Prima-3, Prima-2 dan Prima-1, dan (8) labelisasi produk
prima.
119
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Untuk mempercepat penerapan GAP/SOP dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1)
Mendorong terwujudnya Supply Chain Management (SCM), (2) Merubah
paradigma pola produksi menjadi market driven, (3) Mendorong peran
supermarket, retailer, supplier, dan eksportir untuk mempersyaratkan mutu dan
jaminan keamanan pangan pada produk, (4) Penyediaan tenaga pendamping
penerapan GAP, (5) Melakukan sinkronisasi dengan program instansi terkait
lainnya, (6) Perumusan program bersama instansi terkait lainnya dan melakukan
promosi, (7) Target kuantitatif pencapaian kebun GAP tercantum dalam Renstra
Departemen Pertanian, (8) Membentuk dan memberdayakan lembaga sertifikasi
untuk melakukan sertifikasi kebun dan produk Prima dan (9) Mendorong
sosialisasi mekanisme sistem sertifikasi dan perangkatnya.
Walaupun belum semua komoditas pertanian di Indonesia sudah menerapkan
GAP dalam pengembangan agribisnisnya, namun penerbitan Permentan tersebut
merupakan sebuah langkah maju dan merupakan dasar hukum yang jelas atas
pelaksanaan GAP di Indonesia. Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat pun
para petaninya belum sepenuhnya menerapkan GAP. Avendano dan Calvin
(2006) menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat melalui Food and Drugs
Administration (FDA) baru menerbitkan panduan GAP bagi para petani untuk
meminimalkan resiko mikrobia bagi buah segar dan sayuran pada tahun 1998.
FDA bahkan sampai saat ini masih memberlakukan GAP bersifat Voulentary atau
sukarela dan belum menjadi kewajiban. Menurut catatan FDA hingga 2002 baru
29 persen petani di AS yang sudah menerapkan GAP dalam praktek budidaya
pertanian, dan sekitar 51 persen lainnya baru dalam tahap persiapan menuju GAP.
120
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Penyebab belum diterapkannya GAP berbagai negara adalah mahalnya biaya yang
harus dikeluarkan untuk menerapkannya.. Menurut Woods dan Suzanne (2005)
saat melakukan penelitian dalam menghitung biaya yang dikeluarkan untuk
melaksanakan Good Agricultural Practices dalam budidaya tanaman strawberry
di sembilan negara bagian di Amerika, ternyata penerapan GAP untuk tanaman
strawberry dibutuhkan biaya berkisar pada US$ 288 /ha/musim tanam. Biaya
tersebut antara lain untuk penyediaan toilet dan tempat cuci tangan di sekitar
lahan bagi pemetik strawberry baik untuk pekerja maupun pengunjung, pelatihan
hygiene, pengepakan dan sanitasi pendingin, pennggunaan baki sekali pakai
apabila diperlukan, monitoring penggunaan air untuk irigasi dan pengembangan
rencana penanganan manajemen krisis bagi usaha apabila terjadi keracunan yang
ditemukan dalam makanan.
Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan tentu menjadi kendala besar untuk dapat
diterapkan oleh para petani di Indonesia yang mayoritas masih berkutat dengan
masalah kemiskinan dan lemah dalam SDM terutama dilihat dari tingkat
pendidikan para petani di Indonesia. Untuk menerapkan GAP di Indonesia saat ini
dioptimalkan untuk dilaksanakan oleh perusahaan agribisnis yang berskala besar
dan berorientasi ekspor. Pemerintah sendiri telah membantu penerapan GAP
tersebut dengan SOP khusus pada setiap komoditas pertanian yang hendak
diusahakan, namun baru terbatas pada komoditas hortikultura. Pemerintah juga
telah memberikan penghargaan kepada berbagai kebun buah yang telah
menerapkan standar GAP melalui penghargaan kategori Prima 3, Prima 2 dan
Prima 1 untuk merangsang penerapan GAP bagi kebun hortikultura buah.
121
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Tantangan lainnya adalah rumitnya prosedur penerapan GAP yang harus
diperhatikan oleh perusahaan agribisnis di Inonesia apabila ingin mengekspor
produknya ke luar negeri terutama negara-negara di Uni Eropa maupun Amerika
Serikat. Ender dan Mickazo (2008) menyatakan bahwa negara-negara di Uni
Eropa juga menggunakan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) untuk
diterapkan dalam penilaian GAP. Bahkan The National Advissory Committe on
Microbiological Criteria for Foods yang dimiliki oleh Pemerintah AS juga
menyarankan pemakaian HACCP sebagai alat penilaian dalam keamanan pangan.
Penerapan strategi dasar HACCP pada Good Agricultural Practice (GAP) pada
lahan pertanian meliputi panduan umum yang terdiri dari :
· program perawatan peralatan
· program sanitasi termasuk pada fasilitas pengepakan
· pembersihan akhir musim tanam
· tempat penyucian dan pengepakan
· pelatihan bagi para karyawan
· program penangan hama dan penyakit
· program perawatan gudang
· transportasi dan pengambilan sampel mikrobia
Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pertanian telah mendorong
pemberlakuan praktek-praktek pertanian yang baik dan ramah lingkungan.
Prinsip-prinsip dalam GAP di Indonesia kemudian diselarakan dengan program
pengendalian hama terpadu (Integrated Pest Management) dan pengelolaan
tanaman terpadu (Integrated Crop Management). Pendekatan pengelolaan ini
penting untuk perbaikan dan pengelolaan pertanian dalam jangka panjang. Fitur
122
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
kuncinya adalah penggunaan yang hati-hati terhadap produk agrokimia termasuk
pestisida, pupuk kimia, dan zat pengatur tumbuh. Karena itu, GAP memanfaatkan
pengendalian hama, penyakit dan gulma sampai taraf aman yang dikehendaki,
yaitu pada batas biaya ekonomis bagi petani dan bahaya yang minimla bagi
operator, orang lain di sekitarnya dan lingkungan hidup. Hal lain yang bersifat
sentral dan penting adalah adanya jejak audit yang jelas, dengan penyelenggaraan
dokumentasi yang komprehensif untuk seluruh tahapan budidaya, prosesing,
penyimpanan hasil, atau bahan baku industri sehingga dapat dirunut kembali.
Secara praktis hal ini dilakukan melalui penyusuanan protokol, pencatatan dan
pendataan tahapan-tahapan kegiatan GAP termasuk penggunaan pestisida, pupuk
kimia dan zat pengatur tumbuh. Hal ini juga akan menjamin konsumen bahawa
mereka mendapatkan output bahan pangan yang terjamin dan memenuhi standar
kualitas yang tinggi.
Peluang Dan Tantangan GAP bagi dunia Agribisnis di Indonesia
Walaupun implementasi penerapan GAP di Indonesia masih sangat berat, namun
pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang strategis untuk pelaksanaan
GAP tersebut. Apalagi saat ini dasar hukum pelaksanaan GAP baru pada tanaman
budidaya buah-buahan yakni dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 61/Permentan/OT.160/11/2006 tanggal 28 November 2006 yang relatif
masih baru. Namun hal itu ternyata tidak serta merta membuat komoditas
pertanian Indonesia lesu di pasaran eksport, terutama untuk negara-negara
ASEAN. Menurut Hadi dan Mardianto (2004) ekspor Produk Pertanian Indonesia
termasuk mengalami pertumbuhan yang positif terutama pada komoditas
perkebunan, perikanan dan peternakan walaupun pertumbuhan ekspor Indonesia
123
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
ternyata juga negatif terutama untuk produk tanaman pangan. Hal tersebut
ternyata menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk
mengembangkan produk pertanian yang dimilikinya.
Sedangkan untuk beberapa komoditas pertanian terutama hortikultura pemerintah
perlu mempertimbangkan untuk memberikan proteksi untuk melindungi produk
pertanian Indonesia hingga mampu menerapkan GAP. Hal tersebut bertujuan agar
para petani di Indonesia dapat menyesuaikan dan menerapkan GAP terlebih
dahulu sebelum diadu hasil produksinya dengan negara-negara yang telah maju
teknologi pertaniannya. Pemberian proteksi ternyata juga mampu untuk
meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani di Indonesia. Hadi dan
Saptana (2008) mencontohkan kebijakan proteksi pada jeruk dan bawang merah
secara makro nasional ternyata berpotensi meningkatkan harga grosir, harga
petani, produksi, dan surplus produsen, menurunkan impor, tetapi dilain pihak
juga menurunkan jumlah permintaan, surplus konsumen, dan penerimaan
pemerintah dari pajak impor.
Kesimpulan dan Saran
Penerapan GAP dalam agribisnis akan semakin mendapatkan sorotan di mata
konsumen di masa-masa yang akan datang, terutama untuk pemenuhan pasar di
negara-negara maju. Tuntutan konsumen akan semakin meningkat terhadap
pemenuhan makanan yang aman dan dengan pengolahan budidaya yang
berwawasan lingkungan. Sementara penerapan GAP di Indonesia saat ini belum
akan dapat dilaksanakan secara optimal mengingat besarnya biaya penerapan
GAP pada sistem pertanian serta masih rumitnya prosedur penerapan GAP
melalui HACCP untuk dapat diterapkan pada petani di Indonesia yang mayoritas
124
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
merupakan petani miskin dengan tingkat SDM yang rendah serta kepemilikan
lahan yang rendah pula. Penerapan GAP di Indonesia baru dapat dimungkinkan
pada perusahaan-perusahaan agribisnis dengan skala besar yang telah berorientasi
ekspor terutama pada perusahaan perkebunan dengan komoditas yang telah diakui
kualitasnya di dunia Internasional.
Sedangkan untuk dapat memacu penerapan GAP di Indonesia Pemerintah perlu
menerbitkan landasan hukum penerapan GAP untuk produk lain di luar buah-
buahan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan proteksi sektor
pertanian sambil mendorong penerapan GAP di Indonesia.
125
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
DAFTAR PUSTAKA
Anonymousa. 2018. How to become an Agricultural
Manager?EnvironmentalScience.org.
https://www.environmentalscience.org/career/agricultural-manager.
November 14, 2018.
Anonymousb. 2018. Mengetahui Sifat-Sifat Hasil Pertanian dan Cara
Penanganannya. https://www.pioneer.com/web/site/indonesia/Mengetahui-
Sifat-Sifat-Hasil-Pertanian-dan-Cara-Penanganannya. November 20, 2018.
Anonymousc. 2019. Agricultural Sector in Indonesia. Indonesia-
Investments. https://www.indonesia-
investments.com/culture/economy/general-economic-
outline/agriculture/item378?. January 17, 2019
Anonymousd. 2017. Minyak Kelapa Sawit. Agricultural Sector in Indonesia.
Indonesia-Investments. https://www.indonesia-
investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-
sawit/item166?searchstring=kelapa%20sawit. January 20, 2019.
Hindarti, Sri. 2019. Diktat Mengajar Manajemen Agriisnis. August 31, 2019.
Kurniawan, Ilham Rizki. 2018. Pertanian Organik dan Syaratnya.
https://eventkampus.com/blog/detail/837/pertanian-organik-dan-syaratnya.
November 21, 2018.
Ajmal, Agha Muhammad. 2010. The Increasing Role Of Agribusiness In
Agricultural Economics. Agriculture Corner. DECEMBER 27, 2010 .
http://www.agricorner.com/the-increasing-role-of-agribusiness-in-
agricultural-economics/. November 13, 2018.
Bureau Labor of Statistics. 2018. United States Department of Labor.
https://www.bls.gov/. November 13, 2018.
Downey, Walter David; and Erickson, Steven P. 1087. Agribusiness Management.
McGraw-Hill. 477 p.
FDA. 2018. US Food and Drugs Administration.: Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP).
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/haccp/. November 15, 2018.
Hamdani, Trio. 2017. 31,86 % Peduduk Kerja Indonesia Ada di Sektor
Pertanian. Jum'at 05 Mei 2017 12:41 WIB.
https://economy.okezone.com/read/2017/05/05/320/1683895/31-86-
penduduk-kerja-indonesia-ada-di-sektor-pertanian. November 13, 2018.
126
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Heiman, Amir; Miranowski, John; Zilberman, David; and Alix. Jennifer 2002.
The Increasing Role of Agribusiness in Agricultural Economics. Journal of
Agribusiness 20,1 (Spring 2002):1S30 © 2002 Agricultural Economics
Association of Georgia.
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/14657/1/20010001.pdf. November
13, 2018.
Husnain; Syahbudin, Haris; Styorini, Diah. 2005. Mungkinkah Pertanian
Organik di Indonesia? Peluang dan Tantangan. INOVASI,
Vol.4/XVII/Agustus 2005
https://www.researchgate.net/publication/260553749_Mungkinkah_Pertan
ian_Organik_di_Indonesia_Peluang_dan_Tantangan [accessed Nov 21
2018].
Myanka. 2018. 43 Characteristics of Agricultural Products.
https://www.coursehero.com/file/p1k9kca/43-CHARACTERISTICS-
AGRICULTURAL-PRODUCTS-31-Agricultural-products-differ-in/.
November 13, 2018.
Muhaimin, Wahib dan Sari, Dyana. 2017. Analisis Kebijakan Agribisnis.
Deepublish, Yogyakarta.
Naelufar, Diyah. 2017. Kelaparan di Indonesia Masih Level Serius. Liputan
6, 17 Mar 2017, 19:07 WIB
https://www.liputan6.com/news/read/2890073/kelaparan-di-indonesia-
masih-level-serius. November 13, 2018.
Hartzell, Herri. 2018. Four Functions of Management: Planning, Organizing,
Leading & Controlling. https://study.com/academy/lesson/four-functions-
of-management-planning-organizing-leading-controlling.html November
13, 2018.
KAN. Komite Akreditasi Nasional). 2018. http://kan.or.id/index.php/aboutkan/.
November 21, 2018.
Pragyandeepa. 2019. Role of Agriculture in the Economic Development of
a Country.http://www.economicsdiscussion.net/economic-
development/role-of-agriculture-in-the-economic-development-of-a-
country/4652. January 8, 2019
Schrage, Michael. 2018. Five Categories to Focus Your KPIs.
Big Idea: Strategic MeasurementBlog September 21, 2018 Reading Time:
6 min
https://sloanreview.mit.edu/article/five-categories-to-focus-your-kpis/.
November 15, 2018.
Shibao, Pek. 2015. Why palm oil expanded, and what keeps it growing.
127
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
https://news.mongabay.com/ 26 March 2015. January 20, 2015.
Triyanto, KBT. 2016. Pentingnya Sertifikasi Organik untuk Produk Pertanian.
https://kabartani.com/pentingnya-sertifikasi-organik-untuk-produk-
pertanian.html.. November 21, 2018.
Tong, A-hua. 2018. Factors Influencing Price of Agricultural Products and
Stability Countermeasures. https://ageconsearch.umn.edu/record/137216.
November 1, 2018.
Ward, Nathalee. 2017. Ray Goldberg: The man that coined the term
“agribusiness”. The Weekly Times, May 25, 2017 9:00pm .
https://www.weeklytimesnow.com.au/agribusiness/decisionag/ray-
goldberg-the-man-that-coined-the-term-agribusiness/news-
story/51e013827b75b6e648cd73341dd26ad4. November 13, 2018.
Wiśniewska, Joanna. 2015. THE CONCEPT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN AGRIBUSINESS. Project : The model of network
relationships in agribusiness. https://www.researchgate.net/project/The-
model-of-network-relationships-in-agribusiness. November 15, 2018.
Widotono, Hendri. 2010. Ruwetnya Mengurus Sertifikasi Produk Pangan
Organik. http://hendri-wd.blogspot.com/2010/06/ruwetnya-mengurus-
sertifikasi-produk.html. November 26, 2018.
128
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
129
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3431495
Anda mungkin juga menyukai
- Bahasa Inggris Sistem 52M Volume 1Dari EverandBahasa Inggris Sistem 52M Volume 1Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (40)
- Bahasa Inggris Sistem 52M Volume 3Dari EverandBahasa Inggris Sistem 52M Volume 3Penilaian: 3 dari 5 bintang3/5 (3)
- Everyday IndonesianDari EverandEveryday IndonesianPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (2)
- Buku Prinsip-Prinsip Agronomi Dengan Hasil-Hasil Di IndonesiaDokumen300 halamanBuku Prinsip-Prinsip Agronomi Dengan Hasil-Hasil Di IndonesiaSellia Virgia RBelum ada peringkat
- Kebijakan KesehatanDokumen314 halamanKebijakan KesehatanrajabBelum ada peringkat
- Manajemen AgribisnisDokumen232 halamanManajemen AgribisnisNatalie Netania SulistioBelum ada peringkat
- Cangkok Jambu Biji KristalDokumen39 halamanCangkok Jambu Biji KristalSurya Handayani100% (2)
- Penalaran Umum PDFDokumen41 halamanPenalaran Umum PDFTazkiaKhBelum ada peringkat
- FV - kt.39 16 Sha P Ilovepdf CompressedDokumen57 halamanFV - kt.39 16 Sha P Ilovepdf CompressedWidxs DodyBelum ada peringkat
- Studi Agribisnis Jambu Madu Deli Hijau (Syzygium Aqueum) Di Kecamatan Tenayan Raya Kota PekanbaruDokumen99 halamanStudi Agribisnis Jambu Madu Deli Hijau (Syzygium Aqueum) Di Kecamatan Tenayan Raya Kota PekanbaruAnos VoldigoadBelum ada peringkat
- Laporan Akhir Magang - Nur Holisah - PKCDokumen114 halamanLaporan Akhir Magang - Nur Holisah - PKCNur HolisahFapertaBelum ada peringkat
- Cover, Bab I, Bab II, Dapus Yopi YuansaDokumen19 halamanCover, Bab I, Bab II, Dapus Yopi YuansaAldoBelum ada peringkat
- Strategi Pengembangan AgrowisataDokumen165 halamanStrategi Pengembangan AgrowisataKrampyangan Kota PasuruanBelum ada peringkat
- Dera Grantika Rahayu 143020170 Teknologi PanganDokumen36 halamanDera Grantika Rahayu 143020170 Teknologi PanganGustikaazharBelum ada peringkat
- Pengelolaan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) Bebas PenyakitDokumen47 halamanPengelolaan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) Bebas Penyakitpuan habibahBelum ada peringkat
- Screenshot 2023-09-13 at 11.49.09Dokumen169 halamanScreenshot 2023-09-13 at 11.49.09Nayra RazhwaBelum ada peringkat
- Muhammad Harun Al Rosyid - H04218006Dokumen86 halamanMuhammad Harun Al Rosyid - H04218006Patih SBelum ada peringkat
- 1804 - Proses Cleaning GandumDokumen81 halaman1804 - Proses Cleaning GandumAfi FahmiBelum ada peringkat
- Dasar Agribisnis Tanaman BG KLS X - 230828 - 145835Dokumen224 halamanDasar Agribisnis Tanaman BG KLS X - 230828 - 145835Sieragiel Cayanknya RaniBelum ada peringkat
- CoverDokumen6 halamanCoverSuja AnggestiBelum ada peringkat
- Dewi Yanti Laporan Magang Kewirausahaan Agroindustri 2019Dokumen42 halamanDewi Yanti Laporan Magang Kewirausahaan Agroindustri 2019Dewi YantiBelum ada peringkat
- CoverDokumen8 halamanCoverfitra ramadhaniBelum ada peringkat
- Skripsi Nadhila Shabrina 123020267 PDFDokumen88 halamanSkripsi Nadhila Shabrina 123020267 PDFNurul AtikaBelum ada peringkat
- Laporan PKL Manajemen PemasaranDokumen85 halamanLaporan PKL Manajemen PemasaranHasan Azzaki AlkaskariBelum ada peringkat
- Siti Aisyah Sanurita Proposal LabDokumen24 halamanSiti Aisyah Sanurita Proposal LabSiti Aisyah SanuritaBelum ada peringkat
- Laporan Matph k.4 FixDokumen61 halamanLaporan Matph k.4 FixanggunallwyBelum ada peringkat
- Laporan Kajian Ta 2022 Rizky Ramadhan - 1Dokumen41 halamanLaporan Kajian Ta 2022 Rizky Ramadhan - 1Rizky RamadhanBelum ada peringkat
- F. K - Sertifikat HKI - Ancah CR - BUKU AGROMEDICINEDokumen48 halamanF. K - Sertifikat HKI - Ancah CR - BUKU AGROMEDICINEesty leoBelum ada peringkat
- Usulan Penelitian 2 Yeni Yuliani NPM 4122520410014Dokumen43 halamanUsulan Penelitian 2 Yeni Yuliani NPM 4122520410014Romy SudiawanBelum ada peringkat
- Laporan Studi Lapang Terintegrasi JogjaDokumen66 halamanLaporan Studi Lapang Terintegrasi JogjaFachrun NisaBelum ada peringkat
- 2656-Full TextDokumen70 halaman2656-Full TextAllieccia WijayaBelum ada peringkat
- Proposal PKLDokumen86 halamanProposal PKLDany Kusuma100% (1)
- Yuni Kartika Sari RRD1B017003Dokumen55 halamanYuni Kartika Sari RRD1B017003Citra PramestiBelum ada peringkat
- Demy Avriani - TA (Abstrak-Lampiran)Dokumen8 halamanDemy Avriani - TA (Abstrak-Lampiran)Demy AvriiBelum ada peringkat
- Proposal AsriDokumen34 halamanProposal AsriRudi SusantoBelum ada peringkat
- Laporan Penelitian 2014 30032019Dokumen84 halamanLaporan Penelitian 2014 30032019Yuni ArsihBelum ada peringkat
- Kti Farmasi Kemenkes Ri AcehDokumen74 halamanKti Farmasi Kemenkes Ri Acehir fanBelum ada peringkat
- Buku Pemuliaan Kacang ML Persil Antar Spesies 03-FinalDokumen140 halamanBuku Pemuliaan Kacang ML Persil Antar Spesies 03-FinalrieBelum ada peringkat
- PKL TiaraDokumen72 halamanPKL TiaraTiara Widya PutriBelum ada peringkat
- Pengaruh Sistem Produksi Dan Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usahaindustri Olahan Makanan Berbahan BAKU PISANG (Musa ParadisiacaDokumen103 halamanPengaruh Sistem Produksi Dan Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usahaindustri Olahan Makanan Berbahan BAKU PISANG (Musa ParadisiacaNina SumartinaBelum ada peringkat
- Laporan Penelitian 2021 Rabiatul AdawiyahDokumen55 halamanLaporan Penelitian 2021 Rabiatul AdawiyahAulia Desi purnama sari AuliaBelum ada peringkat
- Haccp FiksDokumen47 halamanHaccp Fikspepi nurainiBelum ada peringkat
- LAPORAN AGROWIDYAWISATA Andika Surya Apriadi (E1J018007) - 1Dokumen16 halamanLAPORAN AGROWIDYAWISATA Andika Surya Apriadi (E1J018007) - 1Andika Surya ApriadiBelum ada peringkat
- Dari Delia Untuk AnaDokumen53 halamanDari Delia Untuk AnaDimas CandraBelum ada peringkat
- Haccp FiksDokumen48 halamanHaccp Fikspepi nurainiBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian Muhammad SupianDokumen39 halamanProposal Penelitian Muhammad SupianSamsul HudaBelum ada peringkat
- Halaman DepanDokumen9 halamanHalaman DepanDaffa SamuderaBelum ada peringkat
- LKTIN - Annisa Wahyu Nur Laily - FULLPAPER-dikonversiDokumen20 halamanLKTIN - Annisa Wahyu Nur Laily - FULLPAPER-dikonversiTomas WahyudiBelum ada peringkat
- 5ae2d5c7515c9ab3a834b65e29affd3cDokumen277 halaman5ae2d5c7515c9ab3a834b65e29affd3cRolita maria sihombingBelum ada peringkat
- LAPORAN K3 Sektor AgroindustriDokumen96 halamanLAPORAN K3 Sektor Agroindustrisri pramiraswariBelum ada peringkat
- Udang VanameDokumen37 halamanUdang VanameRanto ZakariaBelum ada peringkat
- Ince Maulana Ibrahim IsmailDokumen48 halamanInce Maulana Ibrahim IsmailTriana DewiBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum PotonggDokumen25 halamanLaporan Praktikum Potonggsigit hardi49Belum ada peringkat
- Draftlaporankerjapraktik Cintyanursyifa PT - SmartDokumen48 halamanDraftlaporankerjapraktik Cintyanursyifa PT - SmartCintya Ns NatawijayaBelum ada peringkat
- AGROEKOSISTEMDokumen199 halamanAGROEKOSISTEMNurhayati YusufBelum ada peringkat
- PKM PSHDokumen34 halamanPKM PSHFakhri Muhammad ZainBelum ada peringkat
- Olivia Anggita Yusuf P - 170130100011090 - Mikroviro UnairDokumen65 halamanOlivia Anggita Yusuf P - 170130100011090 - Mikroviro UnairoliviaanggitaBelum ada peringkat
- Laporan PKL I (Print)Dokumen65 halamanLaporan PKL I (Print)Nadila AningtyazBelum ada peringkat
- Laporan PKL 2016 USU. Agribisnis. Pertanian. Desa Bingkat. Juli-Agustus 2016Dokumen74 halamanLaporan PKL 2016 USU. Agribisnis. Pertanian. Desa Bingkat. Juli-Agustus 2016Dicky Loyal Cr100% (1)
- Pengelolaan Kebun Raya Daerah Antara Kenyataan Dan Harapan Rachmini Saparita Eki Karsani Apriliyadi Savitri Dyah W I K R Akhmadi AbbasDokumen70 halamanPengelolaan Kebun Raya Daerah Antara Kenyataan Dan Harapan Rachmini Saparita Eki Karsani Apriliyadi Savitri Dyah W I K R Akhmadi Abbasedycoppee603100% (3)
- Lomba LKTI MYRES ALWASILAH LIL-HASANAHDokumen24 halamanLomba LKTI MYRES ALWASILAH LIL-HASANAHsrinursantiBelum ada peringkat
- (Jurnal Manajemen Agribisnis) : Magister Agribisnis Fakultas PertanianDokumen15 halaman(Jurnal Manajemen Agribisnis) : Magister Agribisnis Fakultas PertanianTazkiaKhBelum ada peringkat
- Luht4235 M1Dokumen43 halamanLuht4235 M1TazkiaKhBelum ada peringkat
- Surat Undangan Doa BersamaDokumen2 halamanSurat Undangan Doa BersamaTazkiaKhBelum ada peringkat
- Tari NusantaraDokumen13 halamanTari NusantaraTazkiaKhBelum ada peringkat
- TABEL PENGAMATAN Sel VoltaDokumen1 halamanTABEL PENGAMATAN Sel VoltaTazkiaKhBelum ada peringkat
- Tabel Perbedaan Phylum MolluscaDokumen5 halamanTabel Perbedaan Phylum MolluscaTazkiaKhBelum ada peringkat
- Percobaan Reversible FixDokumen2 halamanPercobaan Reversible FixTazkiaKhBelum ada peringkat
- Ucun2016 Ipa A PDFDokumen6 halamanUcun2016 Ipa A PDFTazkiaKhBelum ada peringkat
- Depan Buku MPDokumen2 halamanDepan Buku MPTazkiaKhBelum ada peringkat
- Alat Alat Zaman Dahulu Manusia PurbaDokumen6 halamanAlat Alat Zaman Dahulu Manusia PurbaTazkiaKhBelum ada peringkat
- Gempa BumiDokumen1 halamanGempa BumiTazkiaKhBelum ada peringkat
- PPU English PDFDokumen48 halamanPPU English PDFTazkiaKhBelum ada peringkat
- PBM PDFDokumen45 halamanPBM PDFTazkiaKhBelum ada peringkat
- NASKAH SOAL REVISI TRY OUT 1 UN - MAPEL - KUR13 - PAKET 2 - KimiaDokumen20 halamanNASKAH SOAL REVISI TRY OUT 1 UN - MAPEL - KUR13 - PAKET 2 - KimiaTazkiaKhBelum ada peringkat
- pERISTIWA PENTING SEKITAR PROKLAMASIDokumen17 halamanpERISTIWA PENTING SEKITAR PROKLAMASITazkiaKhBelum ada peringkat
- Penjajahan Bangsa Portugis Dan Spanyol DiDokumen22 halamanPenjajahan Bangsa Portugis Dan Spanyol DiTazkiaKhBelum ada peringkat
- Rumus Tekanan HidrostatisDokumen2 halamanRumus Tekanan HidrostatisTazkiaKhBelum ada peringkat
- Contoh Puisi LamaDokumen3 halamanContoh Puisi LamaTazkiaKhBelum ada peringkat
- Teori Masuknya Agama Hindu Ke IndonesiaDokumen2 halamanTeori Masuknya Agama Hindu Ke IndonesiaTazkiaKhBelum ada peringkat